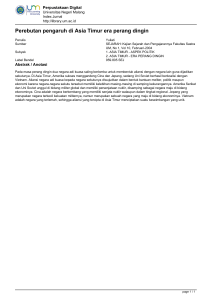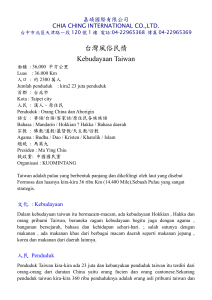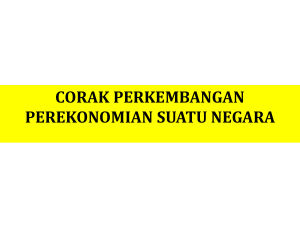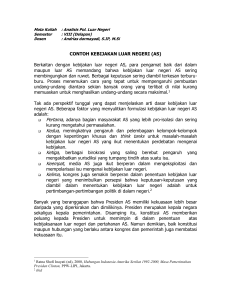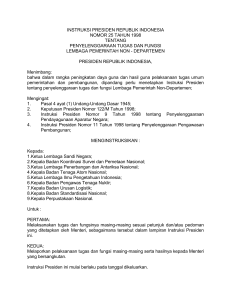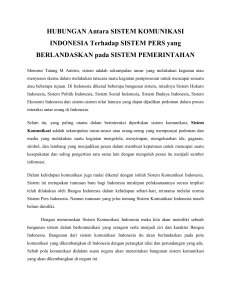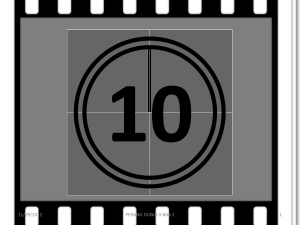Pengantar Pol Pengantar Politik Luar Negeri Cina Cina
advertisement

Pengantar Politik Luar Negeri Cina 1. Tahap-tahap Evolusi Politik Luar Negeri Cina BAB ini menggambarkan secara garis besar tema dan isu-isu politik luar negeri Cina. Sebagai permulaan, kiranya perlu diketahui gambaran singkat evolusi politik luar negeri Cina untuk lebih memahami peran Cina dalam politik dunia. Perlu pula ditunjukkan di sini faktor-faktor yang mempengaruhi politik luar negeri Cina, yaitu faktor geografis, sejarah, ideologi politik, pasang surut politik internal, dan adanya tekanan internasional pada periode tertentu. Perkembangan politik luar negeri Cina sendiri dapat dibagi dalam empat tahap evolusi, yaitu : 1. Masalah perbatasan dan keamanan (1950 — 1953). 2. Silih bergantinya kebijakan militansi dan koeksistensi damai (1954 — 1965). 3. Isolasi selama Revolusi Kebudayaan (1966 — 1968). 4. Kembalinya Cina ke diplomasi konvensional di bawah tekanan internasional serta peningkatan kontak-kontak internasional Cina (1969 — sekarang). Perhatian pada Penyelesaian Masalah Perbatasan dan Keamanan (1950 — 1953. Kebanyakan kegiatan eksternal Cina selama tahun konsolidasi ini tercurah untuk menjaga keamanan perbatasannya dan untuk memperoleh kembali wilayahnya yang hilang, seperti Xizang (Tibet) dan Taiwan. Demi dua tujuan ini, Cina akhirnya terlibat dalam konflik bersenjata di bulan Oktober 1950. Saat itu pasukan Amerika Serikat di bawah komando PBB yang dipimpin oleh Jenderal Douglas Mac Arthur masuk ke Korea Utara dan sudah sampai ke sungai Yalu, yang memisahkan Korea Utara dengan Cina. Cina khawatir kalau kekuatan AS itu akan melintasi Yalu dan masuk Manchuria. Situasi ini mendesak Cina ikut dalam konflik bulan Oktober itu, demi keamanan perbatasannya. Selain itu Cina terlibat dalam konflik juga karena intervensinya ke Xizang untuk mengambil wilayah itu, meskipun India kemudian memprotes tindakan tersebut. Sebelumnya, Cina juga berusaha untuk mengambil kembali Taiwan walau ditentang oleh AS. Sebagai akibatnya, AS menerapkan containment policy terhadap Cina melalui basis-basis pertahannya di Pasifik. Universitas Gadjah Mada Pengarub Politik Dalam Negeri terhadap Politik Luar Negeri Cina (1954 — 1965) Pada periode ini, politik luar negeri Cina diwarnai oleh silih bergantinya semangat berperang dan hidup berdampingan secara damai. Hubungannya dengan negara lain dipengaruhi oleh politik internal Cina yang merefleksikan perubahan gaya kepemimpinan dan strategi pembangunan untuk mencapai tujuan sosialisme dan industrialisasi. Konferensi Jenewa 1954, yang mempertemukan Perdana Menteri Zhou Enlai dengan Menlu AS John F. Dulles dan PM Inggris Anthony Eden, menandai debut Cina dalam diplomasi internasional konvensional. Konferensi ini membahas masalah Indocina dan unifikasi Korea. Di tahun 1955 Zhou Enlai dan PM India Nehru memainkan peran dominan dalam Konferensi Bandung yang dihadiri oleh negaranegara non-blok dan Asia dan Afrika. Konferensi ini menghasilkan lima prinsip hubungan antarnegara `hidup berdampingan secara damai', yaitu (1) saling menghormati kedaulatan dan integritas teritorial, (2) nonagresi, (3) tidak saling mencampuri urusan internal, (4) kesetaraan dan saling menguntungkan, serta (5) koeksistensi damai. Di sini terlihat bahwa politik luar negeri Cina diwarnai oleh kerja sama dan semangat hidup berdampingan secara damai. Ketika perselisihan para pemimpin Cina tentang strategi pembangunan muncul kepermukaan di masa Lompatan Jauh ke Depan (1958 — 1960), postur hubungan luar negeri Cina menjadi militan. Ketegangan memuncak di Selat Formosa selama tahun 1958 karena Cina membombardir kaum nasionalis di lepas pantai pulau Mazu dan Jianmen yang berjarak 12 mil dari daratan Cina. AS menyokong kaum nasionalis dengan Armada Ketujuh-nya. Akibatnya, Cina terpaksa menghentikan serangan dan merundingkan perdamaian dengan AS. Konflik dihentikan dan Cina mulai membangun ekonominya secara moderat pada tahun 1962, setelah kegagalan program Lompatan. Interaksi dengan negara lain meningkat karena membangun Cina perlu bekerja sama dengan negara lain. Pada akhir tahun 1963 dan awal tahun 1965 PM Zhou Enlai mengunjungi empat belas negara di Asia, Afrika, dan Eropa, sementara Presiden Liu Shaoqi mengunjungi negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Pada tahun 1963 politik luar negeri Cina kembali diwarnai semangat hidup berdampingan secara damai. Kebijakan internal membangun sosialisme dan industrialisasi semakin mempengaruhi hubungan kerja sama Cina dengan negara lain. Universitas Gadjah Mada Politik Luar Negeri Cina selama Revolusi Kebudayaan (1966 — 1968 ). Selama Revolusi Kebudayaan bisa dikatakan politik luar negeri Cina berada pada titik terendah karena hubungan luar negeri Cina dengan negara lain tidak harmonis. Walaupun kunjungan dari negara-negara sahabat dan orang-orang terkemuka masih ada, tetapi pemimpin Cina hampir tidak pernah berkunjung ke luar negeri karena di masa ini terjadi kekacauan di dalam negeri (seperti pembantaian orang-orang asing yang ada di Cina dan pertentangan dengan kaum radikal). Hal ini sangat mempengaruhi politik luar negeri Cina dan menjadikannya tidak terarah. Kaum radikal tidak hanya "ingin ikut campur dalam kebijakan luar negeri", tetapi juga "ingin mengambil alih kekuasaan Kementrian Luar Negeri". Keterlibatan AS di Vietnam pada tahun 1965 menjadi pemicu perdebatan tentang ancaman terhadap Cina di perbatasan barat daya. Merembetnya demonstrasi dan kerusuhan hingga ke Hongkong dan Burma pada tahun 1967 mengindikasikan upaya kaum radikal untuk mengekspor pemikiran Mao dan pengalaman revolusioner Cina sebagai tujuan utama politik luar negerinya. Selama periode yang singkat ini Zhou Enlai kehilangan kontrol atas politik luar negeri Cina sehingga ekspor revolusi model Cina ini bukan merupakan kebijakan resmi pemerintah. Cina Kembali ke Diplomasi Konvensional (1969 — 1976). Politik luar negeri Cina yang pragmatis dibentuk untuk memperkuat posisi internasional Cina secara umum dan memperbaiki keseimbangan kekuasaan di Asia. Semangat hidup berdampingan secara damai mewarnai politik luar negeri Cina pasca Revolusi Kebudayaan, termasuk upaya ke arah pemulihan hubungan dengan AS. Penandatanganan Komunike Shanghai oleh Presiden Richard Nixon dan Zhou Enlai pada tahun 1972 menandai kemenangan diplomatic Zhou karena Cina memperoleh dukungan untuk mengatasi ancaman dominasi `imperialisme' Soviet. Cina juga mengindikasikan dukungannya terhadap kehadiran AS di Asia dengan mengurangi kritiknya terhadap perjanjian keamanan antara AS dan Jepang serta basis-basis AS di Pasifik. Pragmatisme politik luar negeri Cina ini mencerminkan dominasi Zhou dalam formulasi politik luar negeri. Yang menjadi patokan utama Zhou adalah pembicaraan detente antara AS dan Uni Soviet. Konsep politik luar negeri Zhou yang baru pada tahun 1975 menganjurkan suatu front bersama di tingkat internasional (tongyi zhaxian) untuk menghadapi detente AS dan Soviet. Selama dekade 1980-an politik luar negeri Cina diarahkan untuk menciptakan sebuah `politik luar negeri yang independen'. Hal ini dipertegas dalam pernyataan- Universitas Gadjah Mada pernyataan yang dibuat oleh Para pemimpin Cina seperti Zhou Enlai dalam perjamuan menghormati Presiden Guinea-Bissau J.B. Vuire pada bulan April 1982 dan Ketua PKC Hu Yaobang pada kongres partai di bulan September 1982. Akhirnya konsep `politik luar negeri yang independen' ini dicantumkan dalam Konstitusi 1982. Setidaknya terdapat tiga interpretasi atas konsep independensi politik luar negeri Cina ini: (1) bahwa Cina tidak akan bersekutu dengan salah satu negara adikuasa, (2) bahwa Cina memperingatkan AS untuk tidak mengandalkan kerja sama dengan Cina guna menghadapi Soviet, dan (3) bahwa Cina hanya mengkaji ulang strategi politik luar negerinya selama ini, yang pada dasarnya anti-Soviet dan proAS. Menlu Zhu Qizhen tegas mengatakan bahwa "Cina menentukan kebijakannya secara independen karena pengalamannya yang dulu, demi kepentingan fundamental rakyat Cina dan seluruh masyarakat internasional." Kemudian PM Zhao, di depan utusan-utusan Kongres Partai Nasional pada April 1987 mengatakan bahwa: "[d]engan memelihara independensi, Cina tidak akan masuk dalam aliansi dengan adikuasa, dan Cina akan berusaha keras untuk membuat dan mengembangkan hubungan yang bersahabat dan kompetitif dengan semua negara berdasarkan lima prinsip hidup berdampingan secara damai. Apa pun masalah yang kita temui dalam kemajuan kita dan apa pun perubahan yang ada dalam situasi internasional, kita akan tetap mengikuti politik luar negeri independen yang damai sampai tahun-tahun berikutnya." Michael Oksenberg, dalam tulisannya di Foreign Affairs 1987, berargumen bahwa konsep ini mencerminkan `nasionalisme Cina yang percaya dire: Menurut Oksenberg, politik luar negeri yang independen ini menjadi dasar bagi Cina menganggap dirinya sebagai aktor utama dalam politik internasional. 2. Tema-tema Utama Politik Luar Negeri Cina Teori Tiga Dunia Konsep Tiga Dunia dikutip dan perkataan Mao pada Februari 1974: Universitas Gadjah Mada "Dalam pandangan saya, Amerika Serikat dan Uni Soviet adalah bentuk Dunia Pertama. Jepang, Eropa, dan Kanada adalah pertengahannya, termasuk Dunia Kedua. Kita termasuk Dunia Ketiga Dunia Ketiga mempunyai penduduk yang sangat besar. Dengan pengecualian Jepang, Asia termasuk Dunia Ketiga. Seluruh Afrika termasuk Dunia Ketiga, dan Amerika Latin juga." Sebenarnya konsep Tiga Dunia ini sudah dirumuskan pada tahun 1955 oleh Zhou Enlai, Nehru, dan Presiden Yugoslavia Joseph Tito di Konferensi Bandung. Deng Xiaoping mengumumkan konsep Cina tentang tiga dunia yang berbeda ini dalam Pertemuan Khusus keenam Majelis Umum PBB, April 1974. Dalam pertemuan itu dijelaskannya empat signifikasi konsep Cina tentang Tiga Dunia : (1) Cina melihat ada perbedaan yang lebar dalam hubungan antara mayoritas masyarakat dunia yang hidup di negara-negara berkembang dengan masyarakat makmur di negara maju. Di dalam pertemuan itu Deng mempertanyakan distribusi kemakmuran bahan mentah dunia, dan menyatakan bahwa negara maju mengeksploitasi masyarakat Dunia Ketiga dengan membayar murah bahan-bahan mentah dari negara berkembang dan menaikkan harga ekspor produk manufaktur yang dijual kepada mereka. (2) Pembedaan dunia menjadi tiga cocok dengan kerangka ideologi tradisional Cina. Cina melihat perjuangan antara Dunia Pertama dan Dunia Ketiga yang didukung oleh Dunia Kedua (Jepang, Kanada, dan Eropa Barat) sebagai perjuangan kelas di masa kini dalam skala dunia. (3) Dengan mendukung Dunia Ketiga Cina bisa mengembangkan koalisi besar untuk memisahkan Soviet dan negara berkembang. Interferensi Soviet di Angola dan tempat lain di Afrika dipandang sebagai imperialisme sosialis yang haws dilawan negara berkembang. (4) Teori Tiga Dunia menggambarkan sikap Revolusi Kebudayaan Cina sebagai model revolusi yang berusaha menandingi yang lain. Cina secara konsisten setia pada dukungannya terhadap Dunia Ketiga, walaupun is bersaing dengan negara berkembang lainnya untuk mendapatkan investasi modal internasional. Antihegemoni Adileuasa Antihegemoni juga menjadi satu objek besar dalam politik luar negeri Cina, khususnya terhadap kedua negara adikuasa yang saat itu banyak melakukan Universitas Gadjah Mada pendudukan di beberapa negara. Dalam pandangan Cina, hal itu merupakan ancaman besar bagi keamanan dan perdamaian dunia sehingga harus dilawan dengan mendukung negara Dunia Ketiga melalui penciptaan tata ekonomi dunia baru. Sikap antihegemoni adikuasa ini antara lain ditunjukkan dalam disarmament dan kebijakan persenjataan nulir. Detente, SALT, Disarmament dan Perang Bintang Pada akhir November 1974, Ketua Partai Komunis Uni Soviet Leonid Brezhnev secara terbuka menolak tuntutan Cina untuk menarik pasukan Soviet dari perbatasan Sino-Soviet sebagai prakondisi normalisasi hubungan kedua negara. Sementara itu, Menlu AS Henry Kissinger dalam mini luar biasanya di Beijing bertemu dengan Deng untuk membicarakan persetujuan senjata nuklir antara Presiden Ford dan Brezhnev. Menurut Deng, Cina tetap menentang segala pembatasan nuklir dan senjata strategis lainnya antara kedua negara adikuasa. Pada tahun 1975 Cina mengkritik konsep detente yang dibahas dalam pembicaraan SALT (Strategic Arms Limitation Talks). Cina menganggap detente digunakan oleh Soviet untuk menutupi ekspansinya seperti yang ditunjukkan oleh intervensi di Angola. Akhirnya memang detente ini berakhir dengan sendirinya ketika Soviet menginvasi Afghanistan pada tahun 1979. Invasi ini menguatkan keyakinan Cina bahwa Soviet adalah "bangsa sosialis yang imperialis". Dalam sidang khusus MU PBB tentang 'disarmament' Cina mengambil tiga posisi, yaitu : 1. 'Disarmament' dimulai oleh negara adikuasa sendiri. 2. Bahwa 'disarmament' sesungguhnya tidak hanya meliputi senjata nuklir saja, tetapi juga senjata konvensional. 3. Menentang proposal Soviet untuk menyusun suatu konvensi internasional yang menjamin keamanan negara-negara pemilik senjata nuklir. Menurut Cina, konvensi tersebut akan membatasi kapabilitas pertahanan negara kecil dan menengah karena kepemilikan senjata nuklir dimonopoli oleh kedua negara adikuasa saja. Wakil PM Wan Li menegaskan kesungguhan posisi Cina dengan menunjukkan langkah konkret Cina berupa deklarasi penghentian tes nuklir di atmosfer dan dukungannya terhadap suatu zona bebas nuklir. Di tahun 1987, Cina mulai mengemukakan keberatannya terhadap perlombaan senjata di luar angkasa. Cina menganggap Strategic Defense Initiative (diterjemahkan sebagai Perang Bin-tang) sebagai rencana AS untuk Universitas Gadjah Mada mengembangkan military industrial complex-nya. SDI juga akan memancing reaksi Soviet untuk memperkuat pertahanan misi balistiknya. Kapabilitas Nuklir Cina, Peluncuran Satelit, dan Zona Bebas Nuklir Pada tahun 1957 Cina memulai program berbiaya tinggi untuk membangun kekuatan militer, terutama misil dan peralatan otomik. Program ini menimbulkan debat panjang dalam partai maupun militer karena faktor tingginya biaya dan tidak adanya bantuan Soviet untuk pengembangan senjata nuklir. Namun bagi Cina, program ini merupakan contoh nyata kemandirian dan ketegasan sikapnya. Pada tahun 1970 Cina meluncurkan satelitnya yang pertama. Sepuluh tahun kemudian Cina juga meluncurkan ICBM yang diarahkan ke Pasifik Selatan. Pada tahun 1981, Cina menambah tiga satelit baru yang dilengkapi dengan sistem peringatan dini untuk menghadapi kemungkinan serangan misil nuklir Soviet. Meskipun kemajuan iptek Cina masih tertinggal, namun program nuklir dan ruang angkasanya terus meningkat sehingga Cina harus dikategorikan sebagai salah satu negara nuklir. Meski telah masuk ke dalam 'klub nuklir' yang eksklusif, Cina tetap konsisten menentang larangan tes nuklir dan traktat nonproliferasi. Menurut Cina, traktat itu dirancang oleh negara adikuasa untuk menghambat penguasaan nuklir oleh negara berkembang. Cina juga emoh mengakui traktat itu karena program nuklirnya diyakini murni untuk tujuan pertahanan semata. Perkembangan kapabilitas nuklir Cina tidak hanya mengubah perimbangan kekuasaan di Asia, tetapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa setiap pembicaraan kontrol senjata, misalnya SALT, tidak akan berarti tanpa keterlibatan Cina. Ada tiga perkembangan terakhir yang menjadi perhitungan dalam kekuatan nuklir Cina : 1. Program peluncuran roket berdasarkan kontrak roket Long March 3. 2. Dukungan Cina terhadap zona bebas nuklir. 3. Pernyataan Cina pada pertengahan tahun 1980-an bahwa Cina tidak lagi melakukan tes nuklir di atmosfer. Motivasi pernyataan ini adalah perlunya reduksi ketegangan dalam hubungan Sino-Soviet. 3. Konflik Sino-Soviet Pada awalnya, hubungan Sino-Soviet secara formal ditandai dengan perjanjian perdamaian dan persahabatan yang kemudian pecah pada tahun 1953 — 1954 karena penolakan Soviet atas permintaan Cina untuk menghadapi Universitas Gadjah Mada containment policy AS di Asia. Titik balk krisis hubungan ini adalah pada 1958 ketika Soviet menolak memberi komitmen melindungi Cina dan ancaman nuklir AS. Sejak tahun 1960 hingga masa Revolusi Kebudayaan, konflik SinoSoviet termanifestasi dalam empat bentuk, yaitu (1) perang kata-kata menyangkut polemik ideologis, (2) kompetisi Cina dengan Soviet dan Taiwan untuk mempengaruhi negara Dunia Ketiga, (3) perang propaganda menentang Soviet melalui isu perang revolusioner, hegemoni adikuasa, detente, dan 'disarmament, serta (4) konflik dan kompetisi untuk mempengaruhi negara komunis lainnya di sekitar Cina. Konflik antara keduanya berlanjut dengan terjadinya perselisihan wilayah perbatasan di utara Sungai Amur, sebelah timur Sungai Ussuri di batas timur laut Cina, dan sebagian lembah Ili di barat laut wilayah Xinjiang. Cina mengklaim bahwa wilayah utara Amur diambil oleh Tsar Rusia pada tahun 1860, sedangkan lembah Ili diambil oleh tentara Rusia pada tahun 1867 sewaktu muslim Xinjiang memberontak terhadap Cina. Mengenai lembah Ili/Pamir, Cina berpijak pada Traktat St. Petersburg 1884 yang mempertahankan status quo wilayah tersebut. Pada tahun 1979 sebenarnya Soviet telah siap memberikan sejumlah konsesi atas Pamir, namun perselisihan keduanya makin meningkat akibat invasi Soviet ke Afghanistan yang oleh Cina diant.t:ap sebagai membuka akses Soviet ke Cina, Iran, Pakistan, dan Samudera Hindia. Soviet juga menganeksasi koridor Wakhan di Pamir sehingga aksesnya ke Cina dan Pakistan semakin aman. Dengan demikian, Soviet mempengaruhi hubungan antara Cina, India, dan Pakistan. Invasi Soviet ini jelas menghambat hubungannya dengan Cina. Melihat situasi ini, sebenarnya kedua negara tersebut ingin membuat kelonggaran dalam hubungan mereka. Oleh karena itu, mereka berusaha menempuh berbagai macam cara untuk mencapai kesepakatan. Pada tahun 1964 misalnya, negosiasi demarkasi perbatasan dimulai. Namun, pada 1969 terjadi bentrokan memperebutkan pulau Chenpaotao (versi Cina) atau Damansky (versi Soviet). Sebagai akibatnya kedua pihak mengintensifkan kubu instalasi militer mereka di daerah perbatasan. Namun, di sisi lain bentrokan ini juga mendorong diadakannya negosiasi para pejabat tinggi untuk meredakan ketegangan. PM Kosygin dan PM Zhou kemudian menandatangani persetujuan kesepahaman pada tanggal 11 September 1969 di Beijing. Namun pada 1971, sikap Cina terhadap Soviet makin kaku, sementara pada saat yang sama Cina makin dekat dengan AS. Penandatanganan Komunike Shanghai pada 1972 Universitas Gadjah Mada menandai titik balik hubungan AS-Cina sekaligus memburuknya hubungan SinoSoviet. Persetujuan AS-Cina ini menentang upaya hegemoni di Asia Pasifik dan menentang negara-negara lain yang melaksanakan tindakan serupa itu, khususnya Soviet. Ketika Mao meninggal pada 6 September 1976, Soviet mengira bahwa itulah saat yang tepat untuk kembali memperbaiki hubungannya dengan Cina. Tapi hal itu ternyata salah ketika PM Hua Guofeng pada Kongres XI Partai tahun 1977 menyalahkan Soviet atas kebuntuan perundingan Soviet-Cina. Cina tetap bersikeras bahwa bila Soviet ingin memperbaiki hubungan mereka, maka is hams memenuhi prakondisi yang diajukan Cina, yaitu: (1) penarikan mundur pasukan dari daerah perbatasan Cina maupun Mongolia, (2) penghentian bantuan kepada Vietnam, dan (3) penarikan pasukan dari Afghanistan. Macetnya perundingan perbatasan Sino-Soviet mendorong Cina beraliansi lebih dekat dengan AS. Di tengah spekulasi kerja sama militer AS-Cina pada 1980, tekanan tertuju kepada pemerintah Soviet untuk membuka kembali perundingannya dengan Cina. Pada 1982, Brezhnev menegaskan kembali dukungan Soviet terhadap klaim Cina atas Taiwan dan menyatakan bahwa Soviet tidak memiliki klaim apa pun atas teritori Cina. Namun Cina tetap menuntut `tindakan konkret' Soviet — artinya masalah Kampuchea dan Afghanistan juga harus dibicarakan. Untuk mengatasi kemacetan perundingan, dalam pidatonya di Vladivostok pada tanggal 28 Juli 1986 Mikail Gorbachev mengemukakan tiga konsesi Soviet untuk memenuhi prakondisi yang diajukan Cina, walaupun tidak semuanya. Ketiga konsesi tersebut adalah : 1. Janji penarikan mundur enam resimen pasukan Soviet dari Afghanistan pada akhir 1986. 2. Proposal pengurangan pasukan di perbatasan oleh kedua pihak. 3. Janji inisiatif perundingan dengan Mongolia tentang pengurangan pasukan Soviet. Sebagai tambahan, Gorbachev menawarkan proyek pembangunan bersama Sungai Amur. Keinginan Soviet untuk memperbaiki hubungan dengan Cina mungkin dimotivasi oleh keinginannya untuk memperlambat langkah-langkah kerja sama ASCina. Pada tahun 1982, hubungan AS-Cina mengalami kemunduran akibat penjualan senjata AS ke Taiwan. Ketegangan hubungan AS-Cina ini mendorong Soviet untuk mendekat ke Cina. Ketiga negara ini pun menjalankan "permainan tawar-menawar" dalam hubungan triangular mereka. Universitas Gadjah Mada Sebagai kesimpulan, dapatlah dikatakan bahwa pidato Vladivostok Gorbachev merupakan peristiwa penting dalam sejarah hubungan Sino-Soviet yang dapat disamakan dengan pendekatan Nixon terhadap Cina pada tahun 1971. Ada dua faktor yang mungkin dapat mempercepat diterimanya persetujuan pengurangan kekuatan militer sepanjang perbatasan, yaitu: (1) kemungkinan bahwa modernisasi militer Cina akan mencapai titik di mana TPR tidak perlu lagi merasa inferior dalam persenjataan dan mobilitas, serta (2) kerja sama ekonomi dan perdagangan antara Cina dan Soviet yang bertahap namun stabil. 4. Normalisasi Hubungan Cina — Amerika Serikat dan Masalah Taiwan Selama dua puluh tahun AS menerapkan kebijakan 'containment' dan isolasi terhadap Republik Rakyat Cina. Namun pada tahun 1971, kebijakan ini dirasakan tidak praktis lagi dengan masuknya Cina ke PBB. Normalisasi hubungan AS-Cina menjadi agenda utama Presiden Nixon yang sedang berusaha meraih masa jabatan keduanya pada tahun 1972. Era baru hubungan Cina-Amerika dimulai dengan penandatanganan Komunike Bersama yang disebut Komunike Shanghai oleh Presiden Nixon dan PM Zhou Enlai pada tanggal 28 Februari 1972. Komunike ini terdiri dan tiga bagian yaitu : 1. Pandangan AS dan Cina mengenai situasi internasional yang sebenarnya menurut pendapat masing-masing negara tersebut. 2. Diterimanya sejumlah prinsip yang digunakan untuk mengatur hubungan kedua negara. 3. Langkah-langkah yang sudah disetujui untuk mencapai normalisasi hubungan antara kedua negara, termasuk penyelesaian masalah Taiwan. Pada akhirnya dalam komunike tersebut AS mengakui bahwa "hanya ada satu Cina; dan Taiwan adalah bagian dari Cina". Maka berakhirlah perdebatan panjang antara AS dan Cina mengenai status Taiwan. AS akan menarik semua kekuatan militernya jika masalah tersebut dapat diselesaikan secara damai oleh Cina. Namun demikian, perubahan pemerintahan di Washington setelah pemilihan presiden 1976 (dari Nixon ke Carter) mengubah pola hubungan Sino-Amerika. Setelah penangkapan Kelompok Empat dan munculnya kepemimpinan baru di Cina, fokus hubungan Sino-Amerika kembali mempermasalahkan Taiwan. Pada tanggal 18 Agustus 1977 PM Hua Guofeng mengusulkan suatu formula guna mengakhiri kebuntuan hubungan kedua negara. Formula tersebut Universitas Gadjah Mada terdiri atas tiga tindakan yang harus dilakukan AS, yaitu (1) pemutusan hubungan diplomatik dengan Taiwan, (2) penarikan semua kekuatan dan instalasi militer AS dan Taiwan, dan (3) pencabutan Perjanjian Pertahanan Bersama pada tahun 1954 yang ditandatangani AS dan pemerintah Taiwan. Menanggapi formula tersebut, pada tanggal 22 Agustus 1977 Menlu AS Cyrus Vance dikirim menuju Beijing. Deng Mapping kemudian menjelaskan beberapa pokok substansi pembicaraan dengan Vance. Dikatakannya bahwa Cina menolak tawaran Vance untuk membuka hubungan diplomatik penuh dengan Beijing seiring dengan digantikannya kedutaan AS di Taiwan menjadi suatu kantor penghubung. Jelas Cina tidak puas dengan tanggapan AS terhadap formula Hua guna penyelesaian masalah Taiwan. Menindaldanjuti situasi ini, pihak AS kemudian mengutus NSA Zbiegniew Brzezinski ke Beijing. Brzezinski menyatakan bahwa hubungan SinoAmerika berdasar pada tiga kenyataan, yaitu: (1) hubungan keduanya akan sangat bermanfaat bagi perdamaian dan keamanan dunia, (2) AS berkepentingan akan Cina yang kuat dan aman, dan (3) sebaliknya, Cina pun berkepentingan atas AS yang kuat dan aman. Bagaimanapun, kunjungan Brzezinski ini tidak berhasil membuat terobosan baru bagi normalisasi. Bahkan di AS, oposisi terhadap kebijakan AS atas Taiwan makin vokal. Terobosan bagi pemecahan normalisasi hubungan Cina-AS akhirnya terjadi pada bulan September 1978. Carter menyatakan bahwa pihaknya akan mengakui pemerintahan RRC jika Cina mengakhiri desakannya terhadap AS untuk mencabut Mutual Defense Treaty dengan Taiwan. Dad situlah Cina berkesimpulan bahwa "formula Jepang" akan dapat memecahkan kebuntuan normalisasi hubungannya dengan AS. Formula tersebut menyatakan bahwa Cina tidak berkeberatan atas hubungan AS dan Taiwan dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan kebudayaan selama AS mengakui RRC. Maka dilangsungkan sejumlah perundingan rahasia antara Beijing dan Washington. Pada tanggal 1 Januari 1979 tercapai suatu komunike bersama yang berisi dua hal penting berikut: 1. Pengakuan AS atas RRC sebagai satu-satunya pemerintahan Cina yang legal, tetapi hubungan tidak resmi AS dengan Taiwan tetap dipertahankan. 2. Penegasan kembali prinsip-prinsip Komunike Shanghai 1972 tentang antihegemoni, pengakuan Taiwan sebagai bagian dan RRC, dan pengurangan konflik militer di Asia. Universitas Gadjah Mada Pada tahun itu pula kedua pihak saling membuka kedutaan besar. Konsesi yang diperoleh AS dari Cina adalah jaminan penyelesaian masalah Taiwan secara damai dan tidak ditentangnya program AS menjual persenjataan defensif secara selektif ke Taiwan setelah Mutual Defense Treaty dihentikan pada tahun 1980. Kerjasama Strategis Cina-AS Pengakuan AS terhadap RRC pada Januari 1979 mengakhiri konflik 30 tahun antara kedua negara. Satu-satunya faktor terpenting yang melandasi normalisasi hubungan keduanya adalah "obsesi atas ancaman Soviet" seperti yang dikatakan Strobe Talbott. Dasar dari hubungan Cina-AS adalah keinginan untuk mengimbangi ekspansi militer Soviet — ini adalah pendekatan yang "reaktif dan negatif". Konsekuensi yang muncul akibat normalisasi AS-Cina berdasarkan pendekatan anti-Soviet adalah munculnya kembali hubungan kekuatan Cina, Soviet, dan AS sebagai "Politik Segitiga" (Triangular Politics). Namun, pemilihan presiden AS di tahun 1980 kembali menimbulkan kekhawatiran Cina atas masa depan kerja sama strategisnya dengan AS. Apalagi dalam kampanyenya Reagan berjanji untuk meningkatkan status resmi Taiwan. Pada tahun 1981 kepada utusan RRC Reagan menjamin secara pribadi komitmen AS pada perjanjian normalisasi. Penjualan Senjata ke Taiwan dan Masalah Unifikasi dengan Cina Hubungan Cina-AS memasuki realitas sesungguhnya setelah suasana yang baik dari tahun 1979 — 1981: isu penjualan senjata ke Taiwan muncul di permukaan. Pada tahun 1979 Kongres meloloskan Akta Hubungan Taiwan (Taiwan Relations Act) sebagai konsesi atas Deklarasi Unilateral Carter pada bulan Desember 1978 yang mengakhiri Mutual Defense Treaty 1954. Akta ini mengijinkan AS menjual persenjataan defensif ke Taiwan. Dapat ditebak, Cina bereaksi keras terhadap Akta ini. Cina dan AS berbeda pendapat semenjak Komunike Shanghai tahun 1972 di mana Taiwan diakui sebagai bagian dari Cina. Menurut Cina, penjualan senjata yang disahkan dalam Taiwan Relations Act merupakan suatu intervensi urusan dalam negeri Cina. AS menghadapi dilema: melanjutkan penjualan senjata ke Taiwan atau mengatasi hubungannya yang memburuk dengan Cina. Pada bulan Januari 1981 Pemerintah Reagan mengumumkan bahwa AS tidak akan menjual pesawat tempur semacam 5GS atau FXS ke Taiwan. Tetapi Universitas Gadjah Mada pada saat yang sama, sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah diadakan sejumlah konsultasi dengan pemerintah Cina mengenai isu penjualan senjata ke Taiwan pada bulan November 1981. Pada tanggal 17 Agustus 1982 kedua pihak menyetujui Komunike Bersama mengenai persyaratan penjualan senajata ke Taiwan. Namun, AS tidak menetapkan waktu untuk pengurangan penjualan senjata ke Taiwan atau pun tanggal penghentian penjualan senjata. Ketiadaan jaminan AS ini mendorong Cina memformulasikan politik luar negeri yang independen dan tidak tergantung lagi pada bantuan dana maupun teknis dan AS. Kontroversi penjualan senjata ini menunjukkan pula adanya masalah besar tentang unifikasi Taiwan. Beijing menawarkan formula `satu negara, dua sistem' di mana Taiwan dapat tetap kapitalis, namun tawaran ini ditolak oleh Taiwan. Kendati demikian, hubungan dagang tidak resmi antara Cina dan Taiwan terus meningkat. Bahkan pasca tragedi Tiananmen 1989, investasi Taiwan semakin penting bagi Cina. Hubungan Dagang, Pendidikan, dan Iptek AS-Cina Sejak tahun 1986, AS telah menjadi mitra dagang terbesar ketiga setelah Jepang dan Hong Kong, serta merupakan sumber modernisasi teknologi terbesar bagi Cina. Cina mengekspor minyak bumi dan tekstil ke AS dalam jumlah besar. Pada periode 1988 — 1990 ini pulalah Cina mulai menikmati surplus perdagangannya dengan AS — sebuah kondisi yang terus berlangsung hingga kini. Sementara itu, ekspor tekstil terus menjadi sumber masalah perdagangan antara kedua negara. Pada tahun 1983 perselisihan tentang tekstil ini menimbulkan embargo selektif Cina terhadap produk AS. Mengenai bidang pendidikan, telah dilakukan program pertukaran pelajar dan mahasiswa AS-Cina. Sedangkan di bidang iptek terjadi pergeseran kerja sama dan pertanian dan ilmu pengetahuan dasar menjadi telekomunikasi dan teknologi. Pada tahun 1985, Senat menyetujui traktat reaktor nuklir yang mengijinkan pembelian reaktor AS untuk merekonstruksi PLTN Cina. 5. Hubungan Sino-Jepang Sejak 1971 Meskipun pada umumnya negara-negara lain memandang Jepang sebagai negara maju dan terbaratkan, namun Cina menganggap Jepang termasuk Dunia Kedua menurut persepsi Tiga Dunia mereka. Cina memandang perlunya front Universitas Gadjah Mada bersama Dunia Kedua dan Ketiga untuk menghadapi hegemoni adikuasa Dunia Pertama. Peningkatan hubungan Cina dan Jepang mungkin termasuk salah satu prioritas utama dalam politik luar negeri independen Cina. Dalam pandangan Cina, normalisasi hubungan Sino-Jepang merupakan "perjuangan yang panjang" karena pada tahun 1950-an hingga 60-an kontak resmi Sino-Jepang dibatasi oleh kebijakan 'containment' AS dan masalah keamanan Pasifik. Lagipula, secara politik dan ekonomi Jepang mendukung Cina Nasionalis di Taiwan. Untuk menarik kerja sama Jepang, Cina mengambil tiga langkah penting. Pertama, peningkatan kontak dagang melalui perjanjian perdagangan khusus berbasis kontak nonpemerintah dengan "perusahaan-perusahaan yang bersahabat", yaitu perusahaan yang tidak memusuhi Cina, tidak mendukung `kebijakan dua Cina', dan dapat menjalin hubungan normal dengan Cina. Kedua, kontrak jangka panjang mclalui persetujuan Liao-Takasaki pada tahun 1962, dan ketiga, kontrak jangka pendek sebagai suplemen dari kontrak jangka panjang. Pada tahun 1971, partai berkuasa di Jepang Liberal Democratic Party (LDP) mendapat tekanan untuk mengubah kebijakannya atas Cina. Dengan adanya "Nixon Shock", yaitu kunjungan Nixon ke Cina, maka `kebijakan dua Cina' yang diadvokasikan oleh PM Eisaku Sato tidak berlaku lagi. Sementara itu, Zhou menaruh perhatian atas berkembangnya militerisme Jepang yang ditandai dengan dikembalikannya Okinawa kepada Jepang. Cina mengklaim ada sejumlah pulau miliknya yang dianeksasi dalam pengembalian tersebut. PM Tanaka, pengganti Sako, berkunjung ke Beijing pada tahun 1972 untuk mengakhiri hubungan 'abnormal' Sino-Jepang. Dalam pernyataan bersamanya, Jepang mengakui RRC sebagai satu-satunya pemerintah Cina yang legal. Kedua negara juga menyetujui pembukaan hubungan diplomatik penuh serta berjanji untuk tidak akan mencari hegemoni di Asia Pasifik. Yang menarik setelah persetujuan Zhou-Tanaka ini adalah munculnya "formula Jepang" untuk tetap melanjutkan hubungan ekonomi dengan Taiwan secara tidak resmi. Beijing ternyata tidak berkeberatan atas formula ini. Traktat Perdamaian Sino-Jepang Konsekuensi langsung dari persetujuan Zhou-Tanaka adalah berkembangnya hubungan perdagangan antara kedua negara. Sementara itu, traktat persahabatan dan perdamaian tetap mengalami kebuntuan selama hampir enam tahun akibat isu Universitas Gadjah Mada hegemoni Soviet. Cina ingin memasukkan isu tersebut dalam traktat, tetapi Jepang menolaknya karena is sedang merundingkan masalah perikanan dengan Soviet. Setelah masalah perikanan ini teratasi, kebuntuan traktat Sino-Jepang dapat diselesaikan. Jepang kemudian mendorong Cina untuk menyetujui klausul tambahan yang menyatakan bahwa traktat mereka tidak terkait dengan pihak ketiga. Akhirnya perjanjian damai Sino-Jepang ditandatangani di Beijing, 12 Agustus 1978. Kedua negara berjanji menaati 'lima prinsip hidup berdampingan secara damai', yaitu respek atas kedaulatan dan integritas wilayah, nonagresi, tidak campur tangan dalam hubungan internasional, kesetaraan dan hubungan yang saling menguntungkan, serta saling menghormati. Setidaknya, ada lima implikasi dan traktat ini, yaitu (1) berakhirnya permusuhan berkepanjangan antara kedua negara, (2) adanya klausul antihegemoni, yang ditujukan kepada Soviet, merupakan kemenangan bagi Cina, (3) perluasan perdagangan jangka panjang dengan Jepang akan mendukung modernisasi Cina, (4) bahwa masalah Taiwan maupun traktat keamanan dengan AS yang tadinya untuk "membendung" Cina tidak berhasil menghalangi hubungan luar negeri Cina, serta (5) fleksibilitas dan akomodasi Cina menjadi petunjuk bagi strategi normalisasi hubungan SinoAmerika. Ketegangan Hubungan Sino-Jepang Kerjasama Cina-Jepang tidak lepas dari ketegangan. Membanjirnya arus barang-barang elektronik Jepang ke pasaran Cina menyebabkan maraknya demonstrasi pelajar di Beijing pada tahun 1985. Kelompok garis keras pun ikut mengkritik pintu terbuka Deng. Deng bereaksi dengan menegaskan perlunya Jepang meningkatkan impor dan Cina. Ketegangan juga terjadi pada tahun 1987 dalam kasus Asrama Mahasiswa Kokario. Keputusan pengadilan Kyoto untuk menyerahkan Kokario ke pemerintah Taiwan selaku pemilik asli asrama tersebut dianggap oleh Cina sebagai melanggar kedaulatannya. Akibat kasus ini, hubungan Sino-Jepang mencapai titik terendah sejak tahun 1972. Ketegangan lain dipicu oleh ketakutan Cina akan bangkitnya militerisme Jepang. Padahal, Cina juga menegaskan perlunya Jepang memperkuat pertahanannya untuk menghadapi ancaman Soviet. Ketakutan kronis Cina ini muncul kembali pada tahun 1987 ketika Deng menganggap Jepang sebagai "negara chauvinis". Nampaknya Cina ingin menghidupkan kembali kenangan akan Universitas Gadjah Mada kejamnya militerisme Jepang antara tahun 1937-45. Namun pada dasarnya, Cina tetap mendukung perjanjian keamanan AS-Jepang. Jepang juga tetap aktif berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi Cina sebagai bagian dan upaya mendukung keamanan regional. Universitas Gadjah Mada