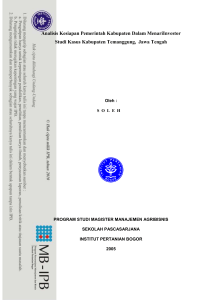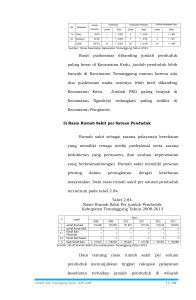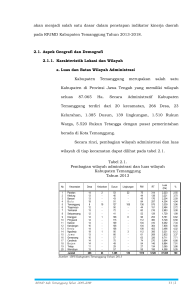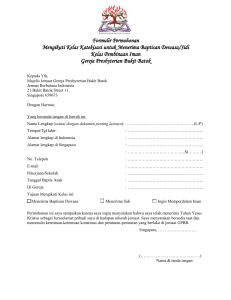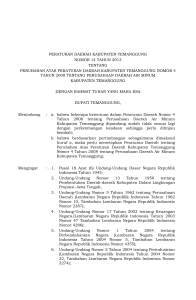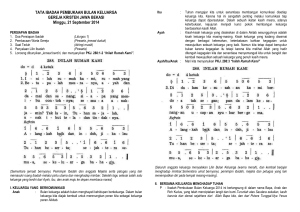Kekerasan Atas Nama Agama, Tindakan Fatal
advertisement
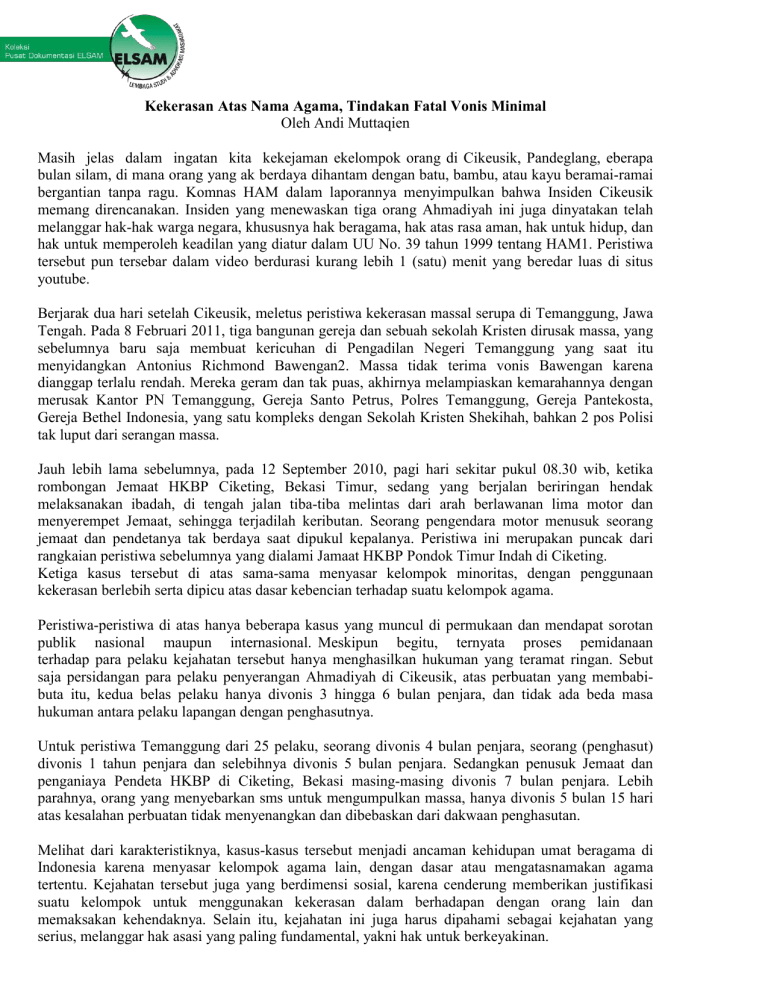
Kekerasan Atas Nama Agama, Tindakan Fatal Vonis Minimal Oleh Andi Muttaqien Masih jelas dalam ingatan kita kekejaman ekelompok orang di Cikeusik, Pandeglang, eberapa bulan silam, di mana orang yang ak berdaya dihantam dengan batu, bambu, atau kayu beramai-ramai bergantian tanpa ragu. Komnas HAM dalam laporannya menyimpulkan bahwa Insiden Cikeusik memang direncanakan. Insiden yang menewaskan tiga orang Ahmadiyah ini juga dinyatakan telah melanggar hak-hak warga negara, khususnya hak beragama, hak atas rasa aman, hak untuk hidup, dan hak untuk memperoleh keadilan yang diatur dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM1. Peristiwa tersebut pun tersebar dalam video berdurasi kurang lebih 1 (satu) menit yang beredar luas di situs youtube. Berjarak dua hari setelah Cikeusik, meletus peristiwa kekerasan massal serupa di Temanggung, Jawa Tengah. Pada 8 Februari 2011, tiga bangunan gereja dan sebuah sekolah Kristen dirusak massa, yang sebelumnya baru saja membuat kericuhan di Pengadilan Negeri Temanggung yang saat itu menyidangkan Antonius Richmond Bawengan2. Massa tidak terima vonis Bawengan karena dianggap terlalu rendah. Mereka geram dan tak puas, akhirnya melampiaskan kemarahannya dengan merusak Kantor PN Temanggung, Gereja Santo Petrus, Polres Temanggung, Gereja Pantekosta, Gereja Bethel Indonesia, yang satu kompleks dengan Sekolah Kristen Shekihah, bahkan 2 pos Polisi tak luput dari serangan massa. Jauh lebih lama sebelumnya, pada 12 September 2010, pagi hari sekitar pukul 08.30 wib, ketika rombongan Jemaat HKBP Ciketing, Bekasi Timur, sedang yang berjalan beriringan hendak melaksanakan ibadah, di tengah jalan tiba-tiba melintas dari arah berlawanan lima motor dan menyerempet Jemaat, sehingga terjadilah keributan. Seorang pengendara motor menusuk seorang jemaat dan pendetanya tak berdaya saat dipukul kepalanya. Peristiwa ini merupakan puncak dari rangkaian peristiwa sebelumnya yang dialami Jamaat HKBP Pondok Timur Indah di Ciketing. Ketiga kasus tersebut di atas sama-sama menyasar kelompok minoritas, dengan penggunaan kekerasan berlebih serta dipicu atas dasar kebencian terhadap suatu kelompok agama. Peristiwa-peristiwa di atas hanya beberapa kasus yang muncul di permukaan dan mendapat sorotan publik nasional maupun internasional. Meskipun begitu, ternyata proses pemidanaan terhadap para pelaku kejahatan tersebut hanya menghasilkan hukuman yang teramat ringan. Sebut saja persidangan para pelaku penyerangan Ahmadiyah di Cikeusik, atas perbuatan yang membabibuta itu, kedua belas pelaku hanya divonis 3 hingga 6 bulan penjara, dan tidak ada beda masa hukuman antara pelaku lapangan dengan penghasutnya. Untuk peristiwa Temanggung dari 25 pelaku, seorang divonis 4 bulan penjara, seorang (penghasut) divonis 1 tahun penjara dan selebihnya divonis 5 bulan penjara. Sedangkan penusuk Jemaat dan penganiaya Pendeta HKBP di Ciketing, Bekasi masing-masing divonis 7 bulan penjara. Lebih parahnya, orang yang menyebarkan sms untuk mengumpulkan massa, hanya divonis 5 bulan 15 hari atas kesalahan perbuatan tidak menyenangkan dan dibebaskan dari dakwaan penghasutan. Melihat dari karakteristiknya, kasus-kasus tersebut menjadi ancaman kehidupan umat beragama di Indonesia karena menyasar kelompok agama lain, dengan dasar atau mengatasnamakan agama tertentu. Kejahatan tersebut juga yang berdimensi sosial, karena cenderung memberikan justifikasi suatu kelompok untuk menggunakan kekerasan dalam berhadapan dengan orang lain dan memaksakan kehendaknya. Selain itu, kejahatan ini juga harus dipahami sebagai kejahatan yang serius, melanggar hak asasi yang paling fundamental, yakni hak untuk berkeyakinan. Deskripsi Umum Putusan Dalam beberapa kasus yang berbasiskan kebencian terhadap suatu kelompok tertentu, khususnya dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan terdapat kesamaan pola yang terjadi dan berlanjut secara terus-menerus. Setidaknya dari contoh kasus yang digambarkan di atas, yakni kasus Ciketing, kasus Cikeusik, kasus Temanggung dapat diambil 4 (empat) kesamaan dalam putusannya. Pertama, putusan dalam kasus-kasus kekerasan yang mengatasnamakan agama tidak pernah memberikan efek jera terhadap para pelaku, karena Majelis Hakim memberikan vonis yang teramat ringan. Padahal, dengan menghukum maksimal tentu dapat memberikan efek jera, sekaligus pada saat bersamaan menjadi tindakan prefentif yang memperlihatkan kepada publik akan kejahatan serius dan layak dihukum berat. Kedua, dalam putusannya, Majelis Hakim kerap t idak bersikap independen dengan mempertimbangkan kedudukan sosial dari terdakwa, dan bahkan menempatkannya menjadi alasan keringanan hukuman. Umumnya, mereka yang dituduh dan dianggap melakukan penghasutan dalam kasus tersebut adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, atau biasa disebut Kyai. Dengan alasan kedudukan mereka yang dibutuhkan oleh masyarakat, hal itu akhirnya ditempatkan sebagai pertimbangan yang meringankan hukuman. Agak aneh mengingat sebagai tokoh masyarakat atau agama, mereka seharusnya menerima hukuman lebih berat. Mereka gagal mencegah anarkisme. Hal ini dikuatirkan memberikan pembenaran terhadap anarkisme, dan akan diikuti oleh masyarakat lainnya. Dalam beberapa putusan pun Majelis Hakim kerap mempermasalahkan akidah yang masuk domain privat seseorang. Hal ini tampak jelas pada kasus Cikeusik. Ketiga, ketiadaan pengungkapan aktor intelektual yang selama ini berada di balik berbagai macam persitiwa kekerasan yang berbasis kebencian terhadap suatu kelompok. Dalam kesaksian- kesaksian persidangan, sebenarnya muncul nama atau ormas tertentu yang dianggap bertanggung jawab atau terlibat dalam rangkaian peristiwa. Misalnya saja peristiwa Cikeusik yang salah seorang saksi menyebut adanya keterlibatan Habib Rizieq4. Begitu juga peranan signifikan mobilisasi massa yang dilakukan Ketua FPI Bekasi Raya dalam rangka penolakan berdirinya Gereja di Ciketing. Setidaknya ini menjadi petunjuk bagi Kepolisian dalam mengusut tuntas kasus-kasus tersebut dan kasus serupa di kemudian hari. Keempat, tiada uraian tentang konteks kekerasan berbasiskan kebencian terhadap suatu kelompok. Memang perlu diakui bahwa proses hukum mempunyai keterbatasan dalam memotret peristiwa secara utuh, namun setidaknya adanya uraian yang memadai tentang konteks kekerasan dan adanya niat pelaku sangat diperlukan demi memberikan gambaran atau bobot kejahatan yang terjadi. Konstruksi peristiwa yang demikian, semakin meneguhkan bahwa banyak diantara peristiwa kekerasan yang mengatasnamakan agama terjadi, juga sebelumnya disertai dengan serangkaian tindakan penghasutan. Ketiadaan konteks tersebut pada akhirnya berdampak pada anggapan bahwasanya peristiwa-peristiwa tersebut adalah semata kriminal biasa tanpa adanya perhatian khusus atau strategi khusus untuk mencegahnya, dan tentunya ketiadaan efek jera dalam vonisnya. Itulah beberapa hal yang tentunya menyumbang kesuburan tindak anarkis dari kelompok yang mengatasnamakan agama dan keyakinan tertentu. Ketiadaan efek jera sampai imparsialitas hakim dengan bersikap independen,sering ditemui dalam persidangan-persidangan kasus tersebut. Proses hukum terhadap kasus-kasus kekerasan yang mengatasnamakan agama selama ini belum mampu memberikan efek jera terhadap para pelakunya. Hal ini diakibatkan karena kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dalam menilai kejahatan yang mempunyai dimensi kebencian kepada kelompok tertentu. Minimnya hukuman akan berakibat bahwa para pelaku tidak merasa perbuatannya salah atau bahkan menyesalinya, sehingga hal itu berpotensi terjadi pengulangan dalam kasus-kasus yang mempunyai konteks yang sama di berbagai tempat. Pengadilan sebagai benteng mengawal hak asasi, seharusnya bisa memberikan hukuman setimpal terhadap para pelaku kekerasan. Jika dalam tuntutannya memang rendah, bisa saja Majelis Hakim menghukum pelaku dengan vonis lebih tinggi dari tuntutan. Putusan Hakim yang memberikan hukuman minim juga sebenarnya adalah dampak dari keseluruhan proses yang memang terlanjur menganggap kejahatan-kejahatan tersebut sebagai “kriminal murni”, dalam arti putusan tersebut tidak hanya hasil dari pendapat Majelis Hakim yang memeriksa perkara, tetapi termasuk juga hasil dari penyidikan di Kepolisian, dan penuntutan yang dilakukan Kejaksaan. Mereka tidak menganggapnya sebagai tindak kejahatan serius, dan berakibat minimnya upaya untuk mengungkapkan fakta di persidangan. Inilah mengapa Pengadilan tidak bisa menjawab soal itu dan menghukumnya dengan teramat rendah. Terlebih lagi ketiadaan kompensasi Negara terhadap para korban dalam kasus-kasus tersebut menambah catatan buruk penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Berdasarkan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil Politik yang diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 tahun 2005 Pasal 2 ayat (3) Kovenan, Negara harus menjamin setiap orang yang hak atau kebebasannya sebagaimana diakui dalam Kovenan tersebut dilanggar, mereka harus mendapatkan pemulihan efektif, bahkan meskipun pelanggaran itu dilakukan oleh orang yang bertindak dalam kapasitas resmi. Pasal tersebut juga menyatakan bahwa pemulihan bagi orang yang dilanggar haknya selanjutnya akan ditetapkan oleh lembaga peradilan, adminsitratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga lain yang berwenang sebagaimana ditentukan oleh sistem hukum Negara tersebut. Jaminan, perlindungan, dan penghormatan HAM tidak mungkin tumbuh dan hidup secara wajar tanpa ada demokrasi dan terlaksananya prinsip negara berdasarkan hukum. Salah satu aspek penting membangun negara berdasarkan hokum adalah memberdayakan sistem penegakan hukum5. Proses penegakan hukum bagi pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama selama ini terlihat tidak menjadi lebih baik, bahkan justru memperlihatkan k etidakmampuan dalam memberikan rasa keadilan bagi para korban. Dalam konstruksi hukum pidana, pihak yang menyuruh lakukan seharusnya dituntut dan diberikan hukuman yang tentu lebih berat dibanding para pelaku lapangan. Selanjutnya hukum pidana sebenarnya menjelaskan, bahwa terkait perbuatan pidana seseorang haruslah tegas pembedaannya dalam tindak pidana, apakah dia seorang pembujuk (uitloker), yang menyuruh melakukan (doen pleger), atau hanya ikut serta melakukan (mendeplegen), sehingga tentunya hukumannya pun tidak dapat disamakan antara masing-masing posisi tersebut. Hal inilah yang gagal dilihat oleh Hakim dalam memutus perkara-perkara tersebut. Minimnya hukuman yang dijatuhkan terhadap para pelaku penyerangan dan kekerasan yang berbasiskan kebencian terhadap suatu kelompok tertentu sangat tidak masuk akal. Karena, secara faktual dan sudah menjadi pengetahuan umum (prima facie) bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa kejahatan biasa (penghasutan, pengrusakan, penganiayaan, dan pengeroyokan), melainkan kejahatan serius (serious crimes) yang memiliki bobot kejahatan tinggi, bahkan menewaskan orang lain dari pihak korban. Secara parsial dalam prakteknya Pengadilan hanya berhasil menemukan pelaku-pelaku lapangan yang bertanggungjawab atas peristiwa, tetapi tidak aktor intelektualnya. Sehingga, wajar saja putusan ini tidak akan memberikan efek jera terhadap kasus- kasus kekerasan yang berbasis kebencian terhadap suatu kelompok agama, seperti yang telah terjadi dalam kasus kekerasan terhadap Jemaat HKBP Pondok Timur Indah di Ciketing Bekasi; kasus penyerangan Jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang dan peristiwa kerusuhan Temanggung. Dalam hal ini, Pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan, tidak berdaya untuk menegakkan hukum dan hak asasi manusia di tengah-tengah kepungan massa anarkis. Idealnya, melalui perangkat aparat penegak hukum baik, Polisi, maupun Jaksa dan berujung di Pengadilan, negara bisa membongkar otak pelaku, yang langsung maupun tidak langsung, termasuk juga pihak-pihak yang selama ini memberikan dukungan akan terjadinya kekerasan. Melihat kecenderungan hal tersebut di atas, Pengadilan sepertinya tak lagi dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk menghalangi merebaknya kekerasan yang mengatasnamakan agama dan mengembangkan kehidupan pluralisme di Indonesia. Apalagi untuk melindungi hak-hak fundamental rakyat Indonesia, khususnya hak untuk beribadah berdasarkan agama dan keyakinan, hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Hal ini telah dijamin UUD 1945, yakni Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: Jaminan Negara tentang kemerdekaan memeluk agama pun dijamin Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Lebih lanjut, Pasal 4 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM juga menyatakan bahwa Hak Beragama merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Begitu juga dalam peraturan- peraturan Internasional6. Hal inilah mengapa hak beragama merupakan hak fundamental. Situasi ketidakmampuan Pengadilan mengungkap dan menghukum setimpal para pelaku kekerasan bukan tidak mungkin justru mendorong dan memberikan pembenaran diam-diam bagi berbagai kelompok untuk melakukan kekerasan dan tindakan sepihak dengan kekerasan kepada kelompokkelompok rentan, yang saat ini marak terhadap agama minoritas.