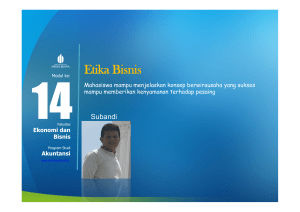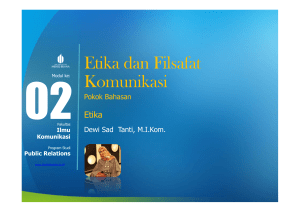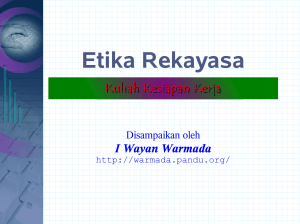etika sosial dan etika agama
advertisement
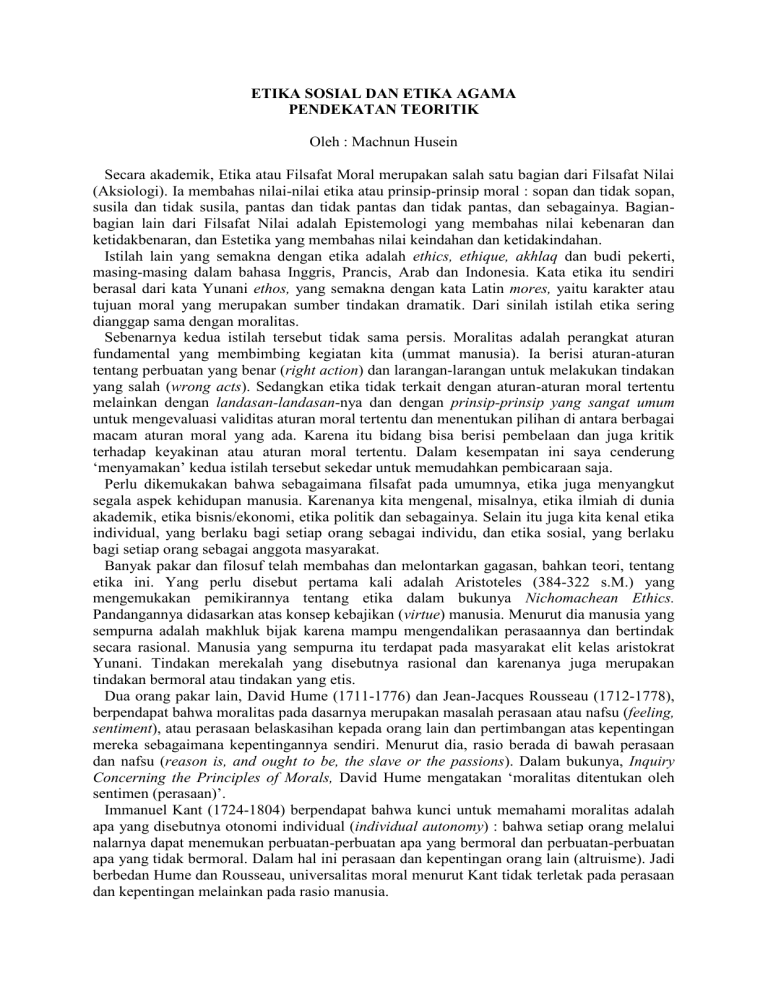
ETIKA SOSIAL DAN ETIKA AGAMA PENDEKATAN TEORITIK Oleh : Machnun Husein Secara akademik, Etika atau Filsafat Moral merupakan salah satu bagian dari Filsafat Nilai (Aksiologi). Ia membahas nilai-nilai etika atau prinsip-prinsip moral : sopan dan tidak sopan, susila dan tidak susila, pantas dan tidak pantas dan tidak pantas, dan sebagainya. Bagianbagian lain dari Filsafat Nilai adalah Epistemologi yang membahas nilai kebenaran dan ketidakbenaran, dan Estetika yang membahas nilai keindahan dan ketidakindahan. Istilah lain yang semakna dengan etika adalah ethics, ethique, akhlaq dan budi pekerti, masing-masing dalam bahasa Inggris, Prancis, Arab dan Indonesia. Kata etika itu sendiri berasal dari kata Yunani ethos, yang semakna dengan kata Latin mores, yaitu karakter atau tujuan moral yang merupakan sumber tindakan dramatik. Dari sinilah istilah etika sering dianggap sama dengan moralitas. Sebenarnya kedua istilah tersebut tidak sama persis. Moralitas adalah perangkat aturan fundamental yang membimbing kegiatan kita (ummat manusia). Ia berisi aturan-aturan tentang perbuatan yang benar (right action) dan larangan-larangan untuk melakukan tindakan yang salah (wrong acts). Sedangkan etika tidak terkait dengan aturan-aturan moral tertentu melainkan dengan landasan-landasan-nya dan dengan prinsip-prinsip yang sangat umum untuk mengevaluasi validitas aturan moral tertentu dan menentukan pilihan di antara berbagai macam aturan moral yang ada. Karena itu bidang bisa berisi pembelaan dan juga kritik terhadap keyakinan atau aturan moral tertentu. Dalam kesempatan ini saya cenderung ‘menyamakan’ kedua istilah tersebut sekedar untuk memudahkan pembicaraan saja. Perlu dikemukakan bahwa sebagaimana filsafat pada umumnya, etika juga menyangkut segala aspek kehidupan manusia. Karenanya kita mengenal, misalnya, etika ilmiah di dunia akademik, etika bisnis/ekonomi, etika politik dan sebagainya. Selain itu juga kita kenal etika individual, yang berlaku bagi setiap orang sebagai individu, dan etika sosial, yang berlaku bagi setiap orang sebagai anggota masyarakat. Banyak pakar dan filosuf telah membahas dan melontarkan gagasan, bahkan teori, tentang etika ini. Yang perlu disebut pertama kali adalah Aristoteles (384-322 s.M.) yang mengemukakan pemikirannya tentang etika dalam bukunya Nichomachean Ethics. Pandangannya didasarkan atas konsep kebajikan (virtue) manusia. Menurut dia manusia yang sempurna adalah makhluk bijak karena mampu mengendalikan perasaannya dan bertindak secara rasional. Manusia yang sempurna itu terdapat pada masyarakat elit kelas aristokrat Yunani. Tindakan merekalah yang disebutnya rasional dan karenanya juga merupakan tindakan bermoral atau tindakan yang etis. Dua orang pakar lain, David Hume (1711-1776) dan Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), berpendapat bahwa moralitas pada dasarnya merupakan masalah perasaan atau nafsu (feeling, sentiment), atau perasaan belaskasihan kepada orang lain dan pertimbangan atas kepentingan mereka sebagaimana kepentingannya sendiri. Menurut dia, rasio berada di bawah perasaan dan nafsu (reason is, and ought to be, the slave or the passions). Dalam bukunya, Inquiry Concerning the Principles of Morals, David Hume mengatakan ‘moralitas ditentukan oleh sentimen (perasaan)’. Immanuel Kant (1724-1804) berpendapat bahwa kunci untuk memahami moralitas adalah apa yang disebutnya otonomi individual (individual autonomy) : bahwa setiap orang melalui nalarnya dapat menemukan perbuatan-perbuatan apa yang bermoral dan perbuatan-perbuatan apa yang tidak bermoral. Dalam hal ini perasaan dan kepentingan orang lain (altruisme). Jadi berbedan Hume dan Rousseau, universalitas moral menurut Kant tidak terletak pada perasaan dan kepentingan melainkan pada rasio manusia. Berbeda dengan Kant, tiga orang filosuf Inggris, Jeremy Bentham (1748-1832), James Mill (1773-1836) dan anaknya John Stuart Mill (1806-1873), mengemukakan pandangan yang mereka sebut utilitarisnisme atau ethical utilitarianism, dengan menempatkan kemanfaatan (utility) atau kesenangan (pleasure) dan kebahagiaan (happiness) sebagai kriteria etika atau moralitas. Menurut mereka, kebaikan tertinggi (the ultimate good) adalah kesenangan. Namun berbeda dengan hedonisme yang hanya mementingkan kesenangan pribadi, mereka menekankan kesenangan pada umumnya, baik kesenangan perorangan, maupun kesenangan orang lain yang terlibat maupun yang tidak terlibat. Mereka inginmembahagiakan sebagian besar orang dan kadang-kadang dengan mengorbankan kebahagiaan yang bersifat sementara. Prinsip utama ‘the greatest good for the greatest number’. Last but not least, pemikiran atau teori etika diberikan oleh Friedrich Nietszche (18441900) dari Jerman, dan para filosuf eksistensialis. Menurut pendapatnya, manusia seharusnya memilih sendiri moralitasnya dan bahwa pilihan ini tidak dapat dijustifikasi dengan cara apa pun sebagaimana dikemukakan oleh para filosuf modern lain. Menurut Nietszsche, pemilihan ini mencakup pemahaman retrospektif terhadap moralitas bangsa Yunani kuno, dan kita harus memasukkan sebagian konsep mereka ke dalam konsep kita sendiri. Nietszsche berpendapat bahwa (pemilihan) moralitas ditentukan oleh kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness). Dia menganjurkan untuk kembali ke moralitas Yunani kuno sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles, meskipun dia beranggapan bahwa konsep kewajiban hanya cocok untuk pembantu dan budak yang lemah. Dia menyebutkannya moralitas budak (slave morality) atau moral ternak (herd morality). Menurut dia, sekelompok kecil elit aristokrat Yunani kuno memiliki kekuatan untuk menetapkan moralitas majikan (master morality) yang dengannya mereka mendapatkan kebahagiaan, tetapi orang lain, seperti para wanita, budak dan orang asing, kelompok yang lemah, bisa hidup cukup senang dan melaksanakan kewajiban mereka secara baik, tetapi mereka tidak dapat disebut ‘berbahagia’. Dia tidak percaya bahwa ‘hakikat’ manusia itu sama. Namun dia yakin bahwa setiap orang dapat berusaha mengembangkan diri sehingga menjadi apa yang disebutnya Manusia Sempurna atau Manusia Luar Biasa (Ubermensch). Setiap orang berhak menemukan dan mengikuti berbagai macam nilai dan konsep yang hebat, dan demikian juga moralitas mereka. Karena itu pelajaran satu-satunya yang diberikan oleh Nietszche adalah ‘ikutilah dirimu sendiri, jangan mengikuti saya’. Dia tidak dapat –dan tidak akan- mencoba memberitahu anda bagaimana caranya hidup. Dia hanya menyuruhmu untuk hidup dan meninggalkan pandangan-pandangan yang menurunkan martabat manusia selama berabad-abad. Pandangan-pandangan tersebut di atas pada dasarnya sependapat bahwa etika atau moralitas bersifat manusiawi, artinya bersumber pada sistem nilai manusiawi (human-value system). Perlu dikemukakan bahwa di samping etika manusiawi, juga terdapat etika ilahi yang bersumber pada sistem nilai ketuhanan (divine-value system) yang tertuang dalam firman Tuhan atau jajaran agama. Etika manusiawi biasanya dianut oleh orang-orang sekularis dan humanis yang menganggap Tuhan tidak berhak mencampuri urusan kehidupan atau pergaulan manusia di dunia ini. Bagi mereka berlaku semacam credo : ‘Manusia adalah ukuran dari segalagalanya’ (Man is the meansure of all things). Karena pikiran dan perasaan manusia itu tidak pernah seragam maka nilai dan kriteria mereka pun senantiasa beragam. Itulah sebabnya etika manusiawi bersifat relatif, tidak mutlak (absolut), temporer, tidak abadi, dan tidak universal, karena selalu terkait dengan subjek/masyarakat, kepentingan, lingkungan/lokasi dan waktu. (Morals are relative to paritcular societies, particular interests, particular circumstances, or particular individuals). Sebaliknya, etika ilahi atau etika agama, relatif lebih stabil dan lebih mutlak, dan universal, terutama di kalangan para pemeluk agama-agama langit (samawi) : Yahudi, Nasrani dan Islam. Keterikatan anggota masyarakat terhadap nilai etika atau moralitas dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya adalah homogenitas mereka. Masyarakat yang relatif homogen biasanya sangat ketat berpegang kepada nilai-nilai etika moral yang berlaku. Setiap pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut akan langsung dikenai sanksi atau hukuman : misalnya pengasingan atau pengucilan dari pergaulan atau bahkan pengusiran. Hukuman yang terakhir ini terutama di lingkungan masyarakat di mana nilai-nilai etikanya sudah demikian mengikatnya sehingga menjadi hukum adat (yang tidak tertulis). Pada saat yang sama, mereka cenderung menghalangi masuknya berbagai macam nilai ‘asing’ dari luar sehingga akhirnya mereka menjadi masyarakat yang tertutup (eksklusif). Keadaan dan sikap yang berbeda terjadi di kalangan masyarakat yang heterogen, terutama bagi segi suku, ras, bangsa dan agamanya. Kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat yang heterogen cenderung lebih terbuka terhadap berbagai macam nilai dari mana pun datangnya dan juga lebih responsif terhadap perubahan. Faktor lain yang mempengaruhi keterikatan masyarakat terhadap nilai etika atau moralitas adalah adanya hukum (positif) lain yang bersifat lebih universal dan yang biasanya memiliki perbedaan konsep tentang nilai-nilai tersebut. Kenyataan menunjukkan bahwa Ilmu Hukum sama sekali tidak memperhitungkan nilai-nilai atau norma-norma etika dan moral itu, sehingga pelanggaran terhadapnya tidak dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan yang bersifat nasional ataupun internasional. Hukum dan etika atau moralitas merupakan dua hal yang tidak hanya berbeda, tetapi juga tidak ada sangkut-pautnya satu sama lain. Karena itu, sampai batas tertentu, pada akhirnya hukum ‘tidak bermuatan moral’ dan ‘moral pun tidak menjiwai hukum’. Atau dengan perkataan lain bahwa moralitas tidak ada sangkut-pautnya dengan hukum (morality has nothing to do with law). Sampai batas tertentu, hal ini bisa mengakibatkan semakin berkurangnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum positif pada khususnya. Mereka tidak mematuhi hukum bukan semata-mata karena kekurangtahuan mereka terhadap aturan hukum itu, tetapi juga lantaran hukum itu sendiri kurang atau tidak mencerminkan nilai-nilai etis atau tidak bermoral (amoral) terhadap pelanggaran nilai-nilai etika dan moralitas bukan saja tidak dikenai sanksi oleh hukum tetapi juga kadang-kadang sama sekali tidak diakui keberadaannya. Karena itulah tidak mengherankan bila masyarakat cenderung melakukan ‘main hakim sendiri’ karena merasa tidak puas dengan sanksi hukum yang dikenakan terhadap pelanggaran atau tidak puas dengan sanksi hukum yang dikenakan terhadap pelanggaran atau tindak pidana tertentu. Kenyataan ini tentu saja tidak hanya menarik untuk diamati, tetapi juga perlu dicarikan solusinya, sehingga nilai-nilai etika dan moral yang berlaku itu juga bisa diterapkan sebagai hukum positif, yang bila dilanggar akan dikenai sanksi pula secara hukum. Dengan perkataan lain, konsep dan persepsi lama yang memisahkan nilai-nilai atau norma-norma etika, moral, kesopanan dan sebagainya harus ditinjau ualng sehingga muncul persepsi baru tentang hukum yang benar-benar mencerminkan nilai-nilai yang berkembang dan berlaku dalam masyarakat. Memang ada kecenderungan di kalangan para ahli hukum untuk memasukkan pelanggaran terhadap nilai-nilai etik atau moralitas ke dalam kategori tindak pidana (delik) yang bisa dihukum. Namun ketentuan itu masih dikaitkan dengan catatan, ‘bila ada badan atau individu yang merasa dirugikan dan kemudian mengadukan halnya ke pihak yang berwajib.’ Dengan perkataan lain bahwa pelanggaran itu hanya dimasukkan sebagai ‘delik aduan’ (klacht delicten). Karena itu, perbuatan melanggar nilai etika atau moral yang dilakukan oleh seorang anak tidak bisa dikeni hukuman bila beru sampai ke tingkatan misbehaviour, karena dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan kecuali dirinya sendiri dan keluarganya. Pelanggaran tersebut baru bisa diadukan ke pihak berwajib bila sudah sampai ke tingkat delinquency, kerena sudah ada pihak yang dirugikan. Padahal sebenarnya, disadari atau tidak, tindakan misbehaviour itu muncul kerena kesalahan orang lain, sebutlah orang tua, yang lalai atau gagal mendidik anaknya. Karena itu, perlu dipertanyakan mengapa orang tua yang lalai itu tidak dikenai hukuman. Bukankah secara etis dan moral, orang tua juga bertanggung jawab atas perbuatan tidak sopan anak-anak yang menjadi asuhan dan tanggung jawabnya. Dalam kaitan itulah kiranya perlu dipertanyakan mengapa nilai-nilai etika dan moral itu tidak dimasukkan saja ke dalam hukum (positif), sehingga melanggarannya bisa dikenai sanksi oleh lembaga peradilan yang sah. Etika agama Islam pada dasarnya tidak pernah memisahkan nilai-nilai etis atau moral dari nilai-nilai hukum. Kedua diatur dalam Syari’ah Islam dan mengelompokkan keduanya dalam lima macam kategori : perintah keras (wajib); perintah lunak (sunnah); larangan keras (haram); perintah lunak (makrah), dan kebebasan (mubah). Masing-masing diberi sanksi berupa hukuman tertentu yang bisa dijatuhkan di dunia ini dan imbalan oleh Allah di akhirat kelak berupa pahala ataau dosa besar maupun kecil. Untuk dapat memahami secara lebih jelas esensi etika agama Islam kita perlu memahami keberadaan manusia di muka bumi ini atau, mengetahui, apa maksud Allah mencipata manusia itu. Dalam al-Qur’an dikatakan bahwa manusia dan jin dicipta oleh Allah agar mereka beribadah (mengabdi) kepada-Nya. Secara lebih jelas, al-Qur’an juga menyatakan bahwa penciptaan Adam adalah untuk menjadi khalifah (pengemban amanat) Allah dimuka bumi : yang terdiri dari (1) tidak melakukan pengrusakan (yufsidu fafa) tetapi membangun dan memakmurkan bumi. Dan (2) tidak menumpahkan darah (yasfikud dima’) tetapi melenyapkan permusuhan dan mencipta kedamaian. Ini berarti bahwa etika agama Islam tidak terlepas dari posisi dan misi manusia sebagai pengemban amanat Allah di muka bumi itu. Secara teoretik etika agama Islam bersumber pada system nilai ketuhanan (divine-value system), namun ia tidak mengabaikan system nilai manusiawi (human-value system) selama nilai manusiawi itu tidak bertentangan dengan nilai ketuhanan. Nilai-nilai ketuhanan itu, yang dalam al-Qur’an disebut dengan istilah fujar dan taqwa, secara teologik sudah diilhamkan kepada umat manusia. Karena itu sebenarnya manusia sudah mengenal nilai-nilai baik yang susila, sopan, dan baik maupun yang tidak susila, tidak sopan dan tidak baik itu. Nilai-nilai yang baik di sebut dalam al-Qur’an dengan istilah ma’ruf karena diketahui dan diakui kebaikannya oleh manusia, sedangkan yagn tidak baik disebut dengan istilah munkar, karena diingkari kebaikannya oleh manusia. Adalah kewajiban setiap Muslim untuk menyeberluaskan dan menegakkan nilai-nilai yang ma’ruf dan mencegah nilai-nilai yang munkar. Bahkan bila terdapat kemungkaran dia, secara pribadi maupun secara bersama-sama, diwajibkan memberantasnya, baik dengan tangannya (kekuasaannya), dengan lidahnya (seruannya) ataupun dengan hatinya. Perlu juga disebutkan di sini bahwa kemungkaran itu tidak hanya berupa pelanggaran terhadap nilai-nilai etika social tetapi juga terhadap nilai-nilai etika individual. Oleh karena itu fungsi pemberantasan kemungkaran itu tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang memegang ‘kekuasaan’ dalam arti politis maupun juridis, tetapi juga orang-orang yang secara etis memegang tanggungjawab atas tegaknya nilai-nilai yang ma’ruf tersebut. Dengan perkataan lain pelanggaran nilai yang berupa misbehaviour pun, bukan hanya yang berupa delinquency, perlu dimintakan pertanggungjawabannya. Islam tidak hanya mengenal pertanggungjawaban juridis, tetapi juga pertanggungjawaban etis atau moral. Kullukum ra ‘in wa kullu ra ‘in mas’ulun ‘an ra ‘iyyatih, Demikian sabda Nabi saw. Sumber: Suara Muhammadiyah Edisi 08 2002