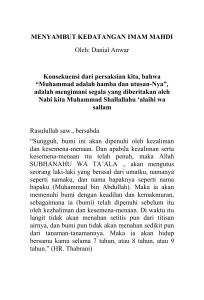1 IMAM SYAFI`I ORANG PERTAMA SEBAGAI
advertisement

1 IMAM SYAFI’I ORANG PERTAMA SEBAGAI MUJTAHID KONTEMPORER Oleh : Drs. Soleman Soleh, M.H.1 A. PENDAHULUAN Agama Islam diturunkan ke dunia ini dalam keadaan sempurna, sehingga tidak ada satu permasalahanpun yang timbul di dunia ini kecuali harus dipecahkan hukumnya. Allah Swt. telah menurunkan syari’at-Nya kepada umat manusia melalui nabi Muhammad Saw. yang berupa Al-Qur’an, agar manusia dapat meyakini, menghayati dan mengamalkannya, untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat. Perkembangan syari’at Islam setelah Nabi Muhammad Saw. hanya merupakan perluasan dan penjabaran terhadap prinsip-prinsip yang telah ditetapkan Allah dalam alQur’an, berupa kaidah-kaidah yang universal, kemudian diterapkan kepada peristiwaperistiwa baru yang muncul dihadapan umat Islam. Hukum Islam akan selalu sesuai dengan perkembangan jaman dan tempat, hal ini sesuai dengan kaidah Ushul yang berbunyi “ Al-hukmu Tagayyurun Bitagayyuril-Amkan wal Azman”. Al-Qur’an jika dilihat dari segi pemahamannya dalam kaitan dengan hukum, ada dua kemungkinan, yaitu nash-nash yang mempunyai nilai Qath’i Ad-Dalalah dan nilai Dzaniy Ad-Dalalah. Qath’i Ad-Dalalah adalah nash-nash yang sudah jelas dan tegas hukumnya, sehingga tidak perlu penafsiran lagi, mengandung arti yang sarih dan bukan lapangan ijtihad. Sedangkag dzany Ad-Dalalah nash-nash yang mempunyai nilai Dzany (umum), sehingga bisa ditafsirkan atau ditakwilkan makna lain dari arti yang tercantum dalam lafadz itu sendiri, dan ini merupakan lapangan ijtihad. Karena itu dalam penetapan hukum dari nash-nash yang dzany, ulama sering berbeda pendapat dan berbeda pula dalam menjabarkan hukum kedalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi meskipun para ulama berbeda pendapat dalam menjabarkan hukum, mereka pada dasarnya ingin mencari kemaslahatan bagi umat manusia, agar manusia beramal sesuai dengan keadilan, rahmah dan hikmah secara keseluruhan untuk di dunia dan akhirat. Hal inilah yang mendorong para Ulama untuk berijtihad dengan sungguhsungguh dalam menjabarkan hukum dari ayat-ayat al-Qur’an/al-Hadits yang bersifat dzany agar sesuai dengan perkembangan jaman dan tempat, sehingga banyak menghasilkan karya yang berupa kitab-kitab, baik berupa kitab fiqh, kitab tafsir, kitab tasauf, kitab tauhid, kitab hadits, kitab ulumul hadits, kitab ushul fiqh, kitab ulumul qur’an, kitab filsafat dan lain sebaganya. Dari sekian banyak para ulama yang telah berijihad untuk menggali hukum dan telah menghasilkan karya-karyanya yang berupa kitab-kitab fiqh, diantaranya adalah Imam Syafi’i. Karya-karya imam Syafi’i yang monumental dalam mengistinbatkan dan menggali hukum dari nash-nash yang bersipat dzany, banyak dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan yang dimilikinya, karena beliau banyak belajar dari satu guru ke guru 1 . Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa 2 lainnya, dari satu negri ke negri lainnya. Beliau pernah belajar di Makkah kepada Muslim bin Khalid Az-Zanji dan Saufyan bin Uyainah, di Madinah kepada Malik bin Annas dan Ibrahim ibnu Sa’ad al-Anshari, di Irak kepada Muhammad bin Hasan Qadhi Yusuf (murid imam Hanafi), di Yaman kepada Umar bin Abi Salamah (mazha Auza’i) dan Yahya bin Hasan (mazhab Leits). Faktor pendukung lainnya adalah faktor geografis dan iklim, faktor kebudayaan dan adat istiadat, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah yang berbunyi : ان اـ ال اـ وا وـ ا ه وــ وم ـ و"ة واـة و ـج ـ + ن ذ- وآ&ـ ی. ف ای م وا زـ ن واـ ل ) ـ ل ا ـل$ـ%ا&ـه ا : ــ;ر وا زـ2ـ ق وا6 ى6 ن- ی+ 7-6 .ـر0ـت واـ2ـ ص وا و4ـ5 ا6 ? ـ دA ـ6 >ــ% ـ2 ا< ا:وا ول ﺱ ـ Artinya : Sesungguhnya keadaan alam, umat, adat istiadat dan akidah, tidaklah selamanya tetap (langgeng) dalam suatu keadaan atau sistem, melainkan akan selalu berubah-ubah sepanjang jaman dan berpindah dari suatu keadaan kepada keadaan lain. Hal tersebut sebagai mana terjadi pada manusia, waktu dan tempat, juga terjadi pada alam, daerah, dan negara. Demikian Sunnah Allah terhadap alam ini. Akibat dari faktor ilmu pengetahuan, faktor geografis dan iklim, faktor kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda, maka hasil ijtihad imam Syafi’i berbeda pula pendapatnya ketika beliau berada di Irak dengan Perbedaan pendapat tersebut tertuang dalam ketika beliau berada di qaul qadim dan qaul Mesir. jadid. Kedua fatwa ini merupakan karya imam Syafi’i yang sangat besar yang kedua-duanya didasari dengan hadits-hadits yang shahih. Imam Syafi’i telah memberikan fatwa dalam qaul qadim dan kaul jadid adalah sebagai jawaban terhadap kondisi dan situasi yang berbeda yang ada pada waktu itu, yang ke dua-duanya mempunyai alasan yang kuat. Oleh karena itu antara qaul qadim dan qaul jadid sering terjadi perbedaan pendapat. Dengan demikian apabila terjadi perbedaan diantara dua qaul yang yang sama-sama dilandasi dengan dalil yang kuat, maka harus ada yang kalah dari salah satu diantara dua dalil tersebut. Menurut Ahmad Ali Al-Anshari (Jld 1:60) “ apabila hadits itu shohih, maka itulah mazhabku. Dalam riwayat lain pendapatku bertentangan dikatakan apabila engkau menemukan dengan hadits Rasulullah Saw. maka ambilah hadits Rasulullah Saw, dan tinggalkanlah pendapatku yang salah itu”. Perkataan Imam Syafi’i tersebut di atas, diambil ketika terjadi dialog antara murid Imam Syafi’i dengan Imam Syafi’i sendiri, waktu itu murid Imam Syafi’i bertanya “ manakah yang dipakai antara qaul qadim dengan qaul jadid kalau terjadi perbedaan pendapat “?. Imam Syafi’i menjawab “ qaul jadid sudah menghapus qaul qadim”, muridnya itu bertanya kembali “ 3 Bagaimana kalau qaul qadim itu adalah hadits yang shahih” ?, Imam Syafi’i menjawab kembali “ kalau begitu apabila hadits itu shahih, maka itulah mazhab saya. Perubahan-perubahan hukum antara qaul qadim dengan qaul jadid Imam Syafi’i pada intinya didorong karena adanya perubahan sosial masyarakat itu sendiri. Seperti adat istiadat dan kebudayaan di Irak berbeda dengan adat istiadat dan kebudayaan di Mesir, sehingga perbedaan tersebut menyebabkan berbeda pula dalam menghasilkan hukum. Oleh karena itu Penulis akan menggambarkan secara singkat skema tentang perubahan qaul qadim dan qaul jadid Imam Syafi’i. Dalam skema tersebut, Penulis juga akan menggambarkan tentang perubahan-perubahannya dari poin ke poin lainnya. Hal ini menandakan Imam Syafi’i sangat tanggap terhadap situasi dan kondisi yang berbeda di satu tempat dengan tempat lainnya, tidak terpaku kepa- da qaul qadim yang telah beliau fatwakan ketika masih di Irak, sehingga karena di Mesir kondisinya berbeda dengan yang ada di Irak, maka beliau mengkaji ulang fatwa tersebut sehingga lahirlah qaul jadid sebagai mana tertera di bawah ini: A B Fiqh dalam Qaul Qadim C Faktor -Geografis -Kebudayaan -Ilmu Pengetahuan Lahirlah Fiqh Dalam Qaul Jadid E F D Qaul Qadim Syari’at Islam Itu sesuai dengan tuntutan jaman, kondisi dan tempat Alternatif Penggunaanya Qaul Jadid Keterangan : Pada kolom A, yaitu fatwa Imam Syafi’i dalam Qaul Qadim ketika beliau berada di Irak, namun ketika beliau berada di Mesir, Imam Syafi’i menemukan kebudayaan (adat istiada) dan geografisnya berbeda dengan yang ada di Irak, sebagaimana tercantum dalam kolom B, akibatnya maka lahirlah fatwa Imam Syafi’i yang baru yang disebut dengan qaul Jadid, seperti tercantum dalam kolom C. Pada kolom D, dicari alternatif penggunaan hukum antara qaul Qadim dengan qaul Jadid, mana yang akan dijadikan sebagai pegangan, karena itu Penulis menjadikan sejajar antara qaul Qadin dengan qaul Jadid berada dalam kolom E, artinya menurut Penulis, bisa saja qaul Qadim 4 dijadikan sebagai sumber hukum, karena yang menentukan berlaku dan tidaknya qaul Qadim adalah kondisi dan situasi daerah itu sendiri, mana yang lebih maslahat untuk diberlakukan sebagaimana tertera dalam kolom F. Dari uraian tersebut di atas, maka timbullah permasalahan pokok yang ingin dibahas oleh Penulis dalam tulisan ini, sehingga akan tergambar dalam sebuah pertanyaan sebagai berikut: 1. Apa yang melatar belakangi timbulnya qaul qadim dan qaul jadid Imam Syafi’i ?. 2. Apakah fatwa qaul qadim dan qaul jadid Imam Asyafi’i hingga sekarang masih tetap relevan ? 3. Bagaimana Implikasinya qaul qadim dan qaul jadid terhadap Pembaharuan Hukum Islam ?. B. LATAR BELAKANG LAHIRNYA QAUL QADIM DAN JADID Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa perbedaan pendapat diantara para Imam Mujtahid dalam mengistinbatkan hukum karena adanya ayat Al-Qur’an atau alHadits yang bersifat dzani. Dalam mazhab Syafi’i selain disebabkan karena ayat alQur’an dan al-Hadits bersifat dzani, banyak pula yang dipengaruhi oleh faktor geografi, faktor kebudayaan dan adat istiadat dan faktor ilmu pengetahuan. 1. Faktor Geografis Faktor geografi sangat menentukan terhadap perkembangan dan pembentukan hukum Islam. Faktor geografis yang sangat menentukan tersebut adalah iklim dan perkembangan daerah itu sendiri. Seperti telah diketahui iklim di Hijaz berbeda dengan iklim di Irak dan berbeda pula dengan iklim yang ada di Mesir, sehingga melahirkan fatwa Imam Syafi’i yang berbeda. Adanya qaul qadim dengan qaul jadid, membuktikan adanya berbedanya iklim dan geografi. HM.Atho Muzhar (Mimbar Hukum No 4 : 23) ulama ahlu ra’yi dan ahlu hadits berkembang dalam dua wilayah geografis yang berbeda. Ulama ahlu rayi dengan pelopornya Imam Abu Hanifah berkembang di kota Kufah dan Bagdah yang metropolitan, sehingga harus menghadapi secara rasional sejumlah persoalan baru yang muncul akibat kompleksitas kehidupan kota, maka Imam Abu Hanifah dan para muridnya menulis kitab-kitab fiqh yang lebih mendasarkan kepada ra’yu. Sebaliknya Imam Malik bin Anas yang hidup di Madinah yang tingkat kompleksitas hidup masyarakatnya lebih sederhana, ditambah kenyataan banyaknya hadits-hadits yang beredar di kota ini, cendrung banyak menggunakan hadits ketimbang rasio atau akal”. Pendapat Atho Mudzhar di atas, menunjukan bahwa berbeda geografis kota akan menentukan terhadap pembentukan hukum. Kota- kota yang secara geografis dipengaruhi oleh ahli filsafat akan berbeda dalam pembentukan hukum dibanding dengan kota-kota yang secara geografis dipenuhi oleh ahli-ahli tasauf. Kota-kota yang 5 tingkat kompleksitasnya lebih tinggi akan berbeda pula pengaruh hukumnya dengan kotakota yang tidak ada kompleksitasnya. Kota-kota yang modern akan berbeda pula pengaruh hukumnya dengan kota-kota yang sederhana dan tertutup. Artinya tingkat urbanisasi disuatu daerah akan menentukan dalam pembentukan hukum pada daerah itu sendir. Mesir secara geografis lebih subur dibandingkan dengan Irak, karena adanya sungai nil yang selalu meluap, di Mesir air lebih mudah didapatkan jika dibandingkan dengn di Irak. Oleh karena itu dalam masalah yang ada kaitannya dengan air (iklim), seperti thaharah, berwudlu, shalat dalam keadaan tidak ada air dan lain sebagainya, Imam Syafi’i telah mengeluarkan fatwa yang berbeda dengan fatwa sebelumnya ketika di Irak. Yang lebih menitikberatkan kepada penekanan harus dikerjakan, karena menganggap tidak mungkin air tidak didapati. Dengan demikian karena di Mesir dengan gampangnya mendapatkan air, maka dalam keadaan bagaimanapun perintah Allah yang ada kaitannya dengan masalah thaharah harus dikerjakan, sedangkan di Irak yang kurang subur bila dibandingkan dengan di Mesir, agak sulit mendapatkan air, maka perintah Allah bisa saja ditunda atau tidak tikerjakan sama sekali. Salah satu contoh fatwa Imam Syafi’i adalah sebagai berikut: “ Apabila datang waktu shalat, sedangkan air dan tanah tidak didapati, maka menurut qaul jadid sholatlah apa adanya dan ulangi shalatnya jika telah didapati air, sedangkan menurut qaul qadim jangan shalat jika air dan tanah tidak ada”. Ke dua fatwa ini jelas sangat berbeda dan saling bertentangan , padahal dalam kasusnya sama, yaitu tidak ada air. Dengan demikian pada intinya para imam mujtahid sangat dipengaruhi oleh keadaan iklim daerah yang ia tempati. Daerah yang panas akan berbeda dengan daerah yang dingin, daerah yang banyak air akan berbeda dengan daerah kering. Begitu juga akan dipengaruhi oleh kemajemukan kota dan kemajuan kota tempat imam mujtahid tinggal. Semakin banyaknya suku bangsa yang hidup disuatu kota akan berbeda dengan kota yang hanya dihuni oleh satu suku bangsa saja, kota yang lebih modern akan berbeda pula dalam menentukan hukumnya bila dibandingkan dengan kota yang sederhana dan tertingal. 2. Faktor Kebudayaan dan Adat Istiadat Faktor kebudayaan dan adat istiadat sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan perubahan hukum Islam. Setelah banyaknya negara-negara yang dikuasai oleh Islam, padahal negara-negara yang dikuasai tersebut telah memiliki kebudayaan-kebudayaan dan adat-istiadat masing-masing yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja, kebudayaan dan adat-istiadat mereka telah menyatu. Oleh karena itu asimilasi (percampuran) antara kebudayaan (adat istiadat) setempat dengan kebudayaan Islam sering terjadi, sehingga menimbulkan akibat lain dari hukum Islam itu sendiri. TM.Hasbi Ash-Shiddieqy (1980: 119) Walaupun masyarakat telah mempunyai kebudayaan-kebudayaan lain yang mempengaruhinya, namun para fuqoha dapat pula 6 menimbulkan pengaruh baru, karena adanya dua faktor yang mempengaruhi perkembangan fiqh di daerah-daerah itu, pertama milieu (lingkungan), ke dua sistem yang ditempuh oleh fuqoha dalam memberikan hukum. Menurut Harun Nasution (1979:14)“ Penafsiran-penafsiran itu lahir sesuai dengan susunan masyarakat yang ada di tempat dan jaman itu muncul. Jaman terus menerus membawa perubahan pada suasana masyarakat. Oleh karena itu ajaran bukan dasar yang timbul sebagai pemikiran dijaman tertentu belum tentu sesuai untuk jaman lain. Begitu juga menurut Abdul Gani Abdullah (2000:22) “ Hubungan antara syari’ah dan peradaban manusia pada satu segi dapat dikatakan kausalistik dengan dasar teoritis bahwa (1). Syari’ah dalam kapasitasnya sebagai respon terhadap proses peradaban, maka antara syari’ah respon, syari’ah terumuskan dan peradaban saling membutuhkan, (2) sebagai karena kebutuhan peradaban manusia, dan arah peradaban manusia bergantung kepada syari’ah itu sendiri. Kebudayaan dan adat istiadat Mesir lebih maju dan lebih modern bila dibandingkan dengan kebudayaan Irak, karena bangsa Mesir pernah dukuasai oleh bangsa Romawi yang kebudayaan dan teknologinya lebih modern pada waktu itu, sedangkan Irak tidak pernah dikuasai oleh bangsa Romawi. Dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan bangsa Romawi telah tertanam pada bangsa Mesir, terutama masalah pergaulan antara satu bangsa dengan bangsa lainnya, oleh karena itu pergaulan sehari-hari di Mesir lebih terbuka, sedangkan di Irak karena belum pernah dikuasai oleh bangsa lain, maka pergaulan sehari-harinya lebih tertutup. Dengan budaya Mesir seperti itulah, maka pada waktu itu Imam Syafi’i memberika fatwa kepada perempuan untuk bebas menuntuk ilmu sebagaimama kaum laki-laki, sehingga pada waktu itu banyak kaum perempuan berduyun-duyun menuntut ilmu pada Imam Syafi’i. Lain halnya ketika tinggal di Irak yang pergaulannya lebih tertutup, sehingga kaum perempuan pada waktu itu tidak diberi kebebasan untuk menutut ilmu, tetapi hanya diperkenankan untuk menutut ilmu sekedarnya saja, itupun kepada muhrimnya atau suaminya. Di Mesir pula Imam Syafi’i menggabungkan dalam satu ruangan antara pelajar laki-laki dengan pelajar perempuan, yang sebelumnya di Irak pelajar laki dengan pelajar perepuan selalu terpisah. Dengan demikian sangat jelas bahwa kebudayaan dan adat istiadat suatu bangsa sangat menentukan dan mempengaruhi terhadap hasil ijtihad seorang mujtahid, hal itu telah buktikan oleh Imam Syafi’i yang merubah hasil ijtihadnya ketika berada di Irak dengan ijtihadnya yang baru ketika berada di Mesir. 3. Faktor Ilmu Pengetahuan Faktor Ilmu Pengetahuan bisa mempengaruhi hasil ijtihad para imam mujtahid dalam menggali hukum dan menentukan hukum. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa Imam Syafi’i seorang yang ahli hadits, karena beliau belajar hadits kepada Imam Malik bin Anas di Madinah, Imam Syafi’i juga seorang ahli ra’yu, karena beliau belajar 7 kepada Imam Abu Yusuf dan Imam Muhamamd bin Hasan murid Imam Abu Hanifah di Irak. Dengan faktor ilmu pengetahuan Imam Syafi’i tersebut, maka hasil ijtihad Imam Syafi’i tidak sama dengan gurunya yang ahli hadits maupun dengan ahli ra’yu. Karena pengetahuan Imam Syafi’i sangat berbeda dengan gurunya yang ada di Madinah sebagai ahli hadits ataupun gurunya yang ada di Irak sebagai ahli ra’yu, tetapi Imam Syafi’i menggabungkan kedua pendapat gurunya itu menjadi fatwanya sendiri. Setelah Imam Syafi’i tinggal di Mesir, pengalaman Imam Syafi’i semakin bertambah dan Imam Syafi’i tetap bertukan fikiran kepada ulama-ulama Mesir. Sehingga setelah berada di Mesir Imam Syafi’i menemukan ada dalil-dalil yang lebih kuat dan lebih shahih bila dibandingkan dengan hasil ijtihadnya ketika masih berada di Irak. Oleh karena itu Imam Syafi’i memandang perlu untuk meluruskan dan meralat kembali fatwa-fatwa beliau ketika masih berada di Irak, karena menganggap fatwa-fatwa beliau yang dikeluarkan di Irak tidak didukung dengan dalil yang lebih kuat. Noel J. Coulson menerangkan (1987:62-63) “ Imam Syafi’i merupakan pembaharuan yang cemerlang. Kecemerlangannya tidak teletak pada pengenalan konsef baru, melainkan pada pemberian konotasi (arti) pemahamannya yang baru bagi ide-ide yang sudah ada, serta keberhasilannya menyatukan ide-ide itu samua dalam satu skema sistematik. Begitu juga menurut Ma’ruf Misbah dkk.(1986:28) Menerangkan: “ Bahwa Islam sebagai suatu sejarah yang terbentuk dari cara hidup mereka dalam mengamalkan ajaran yang mutlak itu. Islam dalam sejarah dan budaya, pemikiran inilah yang bisa berubah-rubah sesuai dengan kemajuan berfikir moral manusia itu sendiri. Ilmu pengetahuan seorang imam mujtahid akan menentuka terjadinya perubahan dalam pembentukan hukum Islam. Sebagai contoh Imam Malik bin Anas yang ahli Hadits fatwanya berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang ahli Ra’yu, sekalipun dalam kasus yang sama. Hal yang sama telah dipraktekan oleh Imam Syafi’i sendiri, ketika beliau di Hijaz Imam Syafi’i memberikan fatwa yang dilandsai dengan d alil-dalil alQur’an dan As-Sunnah, tidak dilandasi dengan ra’yu, karena pada waktu itu beliau belum mengetahui tentang ra’yu, tetapi ketika beliau sudah berada di Irak dan telah belajar tentang ahli ra’yu, maka beliau merubah sendiri fatwanya yang dilandasi dengan pendapat ra’yu, begitu juga setelah di Mesir beliau menemukan hadits yang lebih kuat yang sebelumnya di Hijaz atau di Irak tidak menemukan hadits tersebut, maka beliau merubah kembali fatwa beliau yang telah dikeluarkan di Irak. C. KEBERADAAN FATWA-FATWA IMAM SYAFI’I DALAM QAUL QADIM DAN QAUL JADID Dalan catatan sejarah Imam Syafi’i telah mengeluarkan beberapa fatwa yang berbeda, 1). Fatwa Imam Syafi’i ketika di Hijaz (Makkah dan Madinah) ketika beliau berumur 15 tahun, fatwa ini bertentangan dengan pendapat gurunya (Imam Malik). 2). Fatwa Imam Syafi’i kertika berada di Irak/Bagdad, yang disebut dengan Qaul Qadim. Fatwa ini bertentangan dengan fatwa yang dikeluarkan di Hijaz. 3). Fatwa Imam Syafi’i 8 ketika berada di Mesir, yang disebut dengan Qaul Jadid. Fatwa ini bertentangan dengan fatwa qaul qadim. Akan tetapi perlu diketahui fatwa Imam Syafi’i yang dikeluarkan di Hijaz sudah tidak dapat ditemukan lagi dalam kitab-kitab Imam Syafi’i yang beredar sekarang ini, oleh karena itu Penulis hanya mengemukakan fatwa qaul qadim dan qaul jadid Imam Syafi’i yang masih terdapat dalam kitab-kitab Imam Syafi’i dan tetap hangat dibicarakan orang. Penulis telah menemukan 33 permasalahan yang berbeda antara fatwa qaul qadim dengan qaul jadid dari beberapa kitab Imam Syafi’i, walaupun demikian Penulis hanya akan dikemukakan beberapa permasalahan saja diantaranya sebagai berikut: 1. Hukum Mendatangkan Saksi Pada Waktu Ruju’ Menurut qaul qadim jika suami ingin merujuk kembali istrinya yang telah di thalak raj’i, maka ia harus menghadirkan saksi, sedangkan menurut qaul jadid tidak perlu mendatangkan saksi, karena rujuk adalah hak suami. Qaul qadim beralasan sesuai dengan firman Allah dalam surat ayat 2 surat AthThalak yang berbunyi: ......... ِِ ل ُِْْ َوَأُِا اَ َد َة ٍ َْ ْ َوَأ!ُِْوا َذوَي........ Artinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakan kesaksian itu karena Allah. Dari keterangan firman Allas Swt tersebut di atas, alasan kaul qadim dapat difahami bahwa firman Allah yang terdapat pada surat Thalak berhubungan dengan masalah thalak, oleh karena itu kesaksian disini ada hubungannya dengan akibat dari perbuatan suami yang mentalak raj’i istrinya. Dengan demikian apabila suami yang menghendaki rujuk kembali yang telah mentalak raj’i istrinya, harus pula mendatangkan saksi yang adil, suami yang menghendaki rujuk dengan istrinya harus mengucapkan kata rujuk dihadapan saksi tersebut. Alasan Qaul qadim juga diperkuat dengan hadits Nabi Saw yang terdapat dalam hadits Abu Daud dan Baihaqi ( Ismail Al-Kahlani Juz.3:182) yang berbunyi : (ـ ی&ا)ـ+ ,- ی. ا&)ـ# .ـ/ـ0 أ ﻥ2 ا34 ر#67 #$ ـ&ان# .ـ:ـ=ـ وى&)ـ;ـ- أ!ــ ـى, یــ8و Artinya: Dari Imran bin Husain Ra. Bahwa ia ditanya oleh seorang laki-laki yang menthalak istrinya, kemudan laki-laki tersebut rujuk kembali kepada istrinya dengan tidak ada saksi, maka Imran bin Husain berkata “hadirkanlah saksi ketika menthalaknya dan ketika merujuknya” (HR.Abu-Daud dan Baihaki). Pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Baihaqi, memang jelas sudah bahwa suami yang hendak melakukan thalak, ataupun rujuk kepada istrinya, harus menghadirkan saksi. Artinya tidak syah thalak dan rujuknya jika tidak dihadapan saksi yang adil. Menurut qaul qadim pungsi saksi disini selain sebagai saksi yang melihat 9 telah terjadi rujuk, juga berpungsi sebagai pemberitahuan, dimana saksi bisa mengumumkan atau memberitahukan kepada orang lain bahwa antara A dengan B telah terjadi rujuk. Sedangkan alasan qaul jadid adalah sebagaimana tercantun dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi : ........ً7َْ ِإنْ َأرَادُوا ِإﺹA َ ِ َذBِC # ِدهE &َ ِ$ , F َ7 َأ# ُُ:َُ;ُ$ و...... Artinya : Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika meraka (para suami) menghendaki ishlah…. Dari keterangan firman Allah tersebut di atas, dapat difahami bahwa menurut qaul jadid, suami berhak untuk merujuk kembali istri-istrinya yang telah dithalak dalam masa menanti (iddah), karena pada masa menanti itu yang berhak memberikan nafkah kepada istri adalah mantan suaminya. Pada masa menanti si istri tidak boleh menerima pinangan dari orang lain, tetapi harus menunggu terlebih dahulu sampai masa menanti itu habis, setelah masa menanti itu habis maka si mantan istri tersebut boleh menerima pinangan orang lain. Karena pada masa menanti yang mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada mantan istrinya adalah mantan suaminya, maka mantan suami mempunyai hak pula untuk merujuk kembali mantan istrinya, dengan demikian ketika mantan suaminya ingin merujuk kembali mantan istrinya, tidak perlu lagi menghadirkan saksi, tetapi cukup dengan kata-kata “aku rujuk engkau” atau dengan perbuatan. Disamping itu pula qaul jadid beralasan, bahwa hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Baihaqi yang dijadikan landasahn dalam qaul qadim adalah hadits Marfu’, artinya salah satu perawi dari hadits itu terputus (tidak ada perawinya), pada hadits tersebut tidak disebutkan siapa perawi hadits pada jaman shahabat, hadits itu langsung saja dari Nabi Saw. Oleh karena itu hadits marfu’ tidak bisa dijadikan hujjah atau pegangan dalam menentukan hukum. Qaul jadid juga menerangkan bahwa ada hadits Nabi Saw. yang lebih shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim (Bukhari Juz. 3: 125) yang berbunyi : ـ2 ﺹى3I ـل ا, ا ـ&أ ﺕـ,H ا ﻥ2 ا34 ـ& ر#$ ا#و (ـL ,ـM:) ـ& );ـC J&ـ ;ـ&ـ0و Artinya: Dari Ibnu ‘Umar Ra, bahwa sanya ketika Ibnu ‘Umar menthalak Istrinya, Nabi Saw, berkata kepada ‘Amar. ” Kembalilah dan rujuklah (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim pada intinya tidak ada perintah untuk menghadirkan saksi ketika ‘Amar disuruh rujuk kembali oleh Rasulullah Saw, kepada mantan istrinya. Dengan tidak adanya perintah menghadirkan saksi oleh Rasulullah Saw, maka terdapat isyarat bahwa ketika mantan suaminya ingin merujuk kembali mantan istrinya, tidak perlu lagi menghadirkan saksi. Disamping itu 10 hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ini lebi shahih bila dibandingakan dengan hadits Abu Daud dan Baihaqi, karena qaul jadid didasari oleh hadits-hadits yang lebih kuat dibandingkan dengan qaul qadim, maka yang perlu didahulukan adalah qaul jadid. 2. Tentang Akhir Waktu Sholat Isya Yusuf Fairuzi (Juz.1:52) Awal waktu Isya’ yaitu apabila telah lenyap mega merah, sedangkan akhir waktu Isya’ ada dua pendapat, menurut qaul Jadid sepertiga akhir malam, sedangkan menurut qalu Qadim waktunya sampai seperdua malam. Dalam kasus akhir waktu shalat Isya’ ini, terjadi perselishan dan berbedaan antara qaul qadim dan qaul jadid. Pada qaul qadim akhir waktu shalat Isya’ adalah seperdua malam, sedangkan menurut qaul jadid adalah sepertiga malam. Pada qaul qadim dilandasi dengan hadits Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang berbunyi: Rـ6 ﻥـ3 ة ا;ــء اOـ ﺹـ0 ــ و2 ﺹـى3ـIـ& اـP اﻥ ل اQ اﻥـ#ـ ..اـ Artinya: Dari Anas, beliau telah berkata, Nabi Saw. telah mengakhirkan shalat isya’ sampai seperdua malam (HR. Buhkari). Disamping itu qaul qadim juga didasari dengan hadits lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang berbunyi : J&ـ آن یــ0 ـ و2 ا3 ﺹ2ـل ا0&زة ان ر$ 3$ ا# اـ;ـء ـ.ـIاـم ـ Artinya: Dari Abi Barzah, bahwa Rasulullah Saw. membenci kepada orang yang tidur sebelum melaksanakan shalat isya’. (HR.Bukhari) Pada qaul jadid dilandasi dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar, yang berbunyi : ا;ـءW6 ـ0 ـ و2 ﺹى2ل ا0&رV: ﻥـWـ ذات ـY &ل#$ ا# J ;ـ$ او. اـZ+ [ ذهـ#7 ]ـ&ج اC &ةP8ا Artinya: Dari Ibnu Umar berkata, kami berdiam pada suatu malam sambil menunggu Rasulullah Saw, untuk melaksanakan keluarlah Nabi shalat isya’ yang diakhirkan, bersama kami untuk melaksanakan shalat isya’ lalu yang menginjak sepertiga akhir dari malam atau lebih.(HR. Muslim). Disamping itu, qaul jadid didukung oleh pendapat Syatha Dimyati yang dilandasi dengan hadits Muslim lainnya, yang menerangkan sebagai berikut: &_ـC ع- ا;ــء اىa اى وـbـ$8&واMﺹ8وال اcـ&ه اPd ﻥـ ب ﺕ3^Iوی 11 ةOـ6 ا.ـ6 یـ# ـ3 iـ&یـM واﻥ ﺕـiـ&یMىم ﺕC Q " ـZیf ﺹد ق ."ـ&ىP8 اa وـ.ـP یـ3:7 Artinya: Mesti disunatkan mengakhirkan shalat isya’ sampai kelihatan bayangan kuning dan putih. Artinya waktu isya’ itu sampai terbitnya fajar shadik. karena ada hadits Nabi yang berbunyi “ tidak termasuk melalaikan shalat karena tidur (belum tiba waktu sholat lainnya), tetapi yang dikatakan melalaikan sholat ialah orang yang belum melaksanakan shalat sampai tiba waktu sholat lainnya. Dari uraian tersebut di atas, bahwa dalam qaul qadim waktu akhir shalat isya’ sampai seperdua malam, dengan alasan karena ada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Buhkari yang membenci tidur sebelum shalat isya’. Sedangkan dalam qaul jadid waktu akhir shalat isya’ sampai sepertiga akhir malam, dengan alasan tidur malam untuk mengakhirkan shalat isya’ yang dilanjutkan dengan shalat sunat malam lainnya bukan termasuk melalaikan shalat, sebagaimana yang diterangkan oleh hadits Muslim. Ke dua fatwa Imam Syafi’i tentang akhir waktu shalat sebagaimana tersebut di atas, baik dalam qaul qadim maupun dalam qaul jadid telah terjadi perselisihan dan pertentangan, yang mana kedua-duanya dilandasi dengan hadits-hadits yang shahih. Oleh karena itu untuk lebih jelas lagi perlu dicari dalil yang lebih kuat dan lebih sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada, dari kedua kaul tersebut di atas. Menurut analisa Penulis, bahwa pada qaul qadim adanya kehati-hatian (ikhtiyat), dengan alasan bahwa dengan sebab tidur akhirnya shalat Isya’ menjadi kesiangan sampai waktu shalat subuh tiba, sedangkan shalat isya’ belum dilaksanakan. Inilah yang menyebabkan mengahkirkan shalat isya’ diselingi dengan tidur dibenci. Sedangkan menurut qaul jadid, bagi orang yang sudah biasa menggabungkan shalat Isya’ dengan shalat sunnat lainnya (Qiyamul-Lail) yang diakhirkan pada dua pertiga malam hukumnya sunnat, dengan tidur terlebih dahulu. Dengan alasan karena mengakhirkan shalat isya’ tersebut sekaligus dengan mengerjakan shalat sunnat malam lainnya sampai tiba waktu shalat shubuh, kebiasaan-kebiasaan seperti ini sering dilakukan oleh Rasulullah saw. Mengakhirkan shalat isya’ adalah sunnah hukumnya, bagi orang yang ingin mengerjakan shalat malam (tahajud), yang kemudian dilanjutkan dengan shalat shubuh. Tetapi kita tidak tahu, apakah dalam keadaan tidur pulas akan yakin bisa terjaga dari tidurnya ketika waktu menginjak pada sepertiga akhir malam. Inilah yang membuat kita ragu, apakah kita bisa terjaga dari tidur dengan tepat waktu yang diinginkan, sedangkan dalam amalan yang masih diragukan harus dihindari. Mengerjakan shalat isya’ hukumnya wajib, oleh karena itu tidak masuk akal kalau orang ingin mengerjakan shalat sunnat dengan mengakhirkan yang wajib, padahal masih diragukan apakah bisa jaga dari tidurnya dengan tepat waktu. Yang lebih baik adalah mengerjakan shalat isya’ tepat pada waktunya, kemudian tidur dan bangun ketika waktu menginjak sepertiga akhir malam dilanjutkan dengan sholat malam (tahajud) sampai tiba waktu shalat shubuh. 12 Dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penulis mendahulukan qaul qadim dari qaul jadid, karena sandaran hadits qaul qadim dari segi Perawi hadits lebih tinggi nilainya dari pada hadits qaul jadid, menurut akal qaul qadim lebih diterima, sebab pada dasarnya mengerjakan yang masih diragukan dengan menunda (meninggalkan) yang wajib termasuk pekerjaan yang dilarang. Disamping itu Penulis juga beralasan bahwa dalil yang digunakan oleh qaul jadid berkenaan dengan waktu shahur bulan ramadhan, yang pada waktu itu semua orang sudah terjaga dari tidurnya, seperti hadits riwayat Imam Bukhari di bawah ini: .ـ0 ـ و2 ﺹى3Iـ&وا ـ( اـfـjـ اﻥـ ﺕـ+ 7 aـ$ـ+ #$ ان زیـQ اﻥـ# .Wیk #ـ:ـ0 او#ـjـPـــــ ـل ـ ر$ آa ة ــOـ6ا اى Artinya: Dari Anas sesungguhnya Zaid bin Tsabit menceritakan, bahwa sanya orangorang sedang makan sahur bersama Nabi Saw. kemudian mereka bersamasama melaksanakan shalat, saya ( Zaid bin Tsabit) berkata berapa lama waktu shahur dengan shalat subuh ?, Nabi menjawab selama membaca alQur’an lima puluh ayat atau enam puluh ayat. Maksudnya bahwa, hadits yang dipakai alasan dalam kaul jadid berkenaan dengan kegiatan bulan ramadhan, karena kebiasaan dibulan ramadhan orang-orang sudah bangun untuk shahur sejak sepertiga akhir malam, atau sekitar pukul tiga malam sampai imsak, sebelum datangnya waktu shalat shubuh, yang biasanya orang-orang mengisi waktunya dengan shalat malam (sunnat) atau mengisi dengan tadarusan membavaal-Qur’an yang dilanjutkan dengan shalat subuh. Jadi kegiatan tersebut sematamata pada bulan ramadhan, bukan pada malam selain di bulan Ramadhan. 3. Tentang Melakukan Shalat Dalam Keadaan Tidak Ada Air dan Tidak Ada Tanah ـ ویـ;ـ7 [ـj7 3 ـ.6 یـ, ةOـ6ـ&ﺕ اl7 و$ ﺕـ&ا8 ـ یـ_ـ ء و#و ـ&اب وهـ ا=ـ ی: یـ_ـ اـء وا3:ـ7 .ـ6ی8 . وه اـ_ـیـJاذا او)ـ Artinya: Apabila orang tidak mendapatkan air dan tanah, kemudian datang waktu shalat, menurut qaul Jadid shalatlah apa adanya dan mengulangi jika telah mendapatkan air dan tanah. Sedangkan menurut qaul Qadim tidak wajib shalat, sampai didapati air dan tanah . Kedua fatwa Imam Syafi’i tersebut di atas, terjadi perselisihan dan saling berlawanan, menurut qaul qadim tidak perlu melakukan shalat jika dalam keadaan tidak ada air dan tidak ada tanah, sedangkan menurut qaul jadid jika tidak ada air dan tidak ada tanah, tetap malakukan shalat apa adanya, dan mengulangi shalatnya jika telah ditemukan air dan tanah. Kedua fatwa Imam Syafi’i tersebut di atas, baik qaul qadim maupun qaul jadid, memang Penulis tidak menemukan hadits Nabi Saw, yang secara khusus 13 menguatkan kedua fatwa Imam Syafi’i tersebut. Oleh karena untuk memecahkan masalah ini Penulis akan mencoba mencari analogi-analogi yang bisa diterima oleh akal. Atau mencari pendapat para pakar yang menguatkan ke dua fatwa tersebut di atas, kemudian mencari fatwa mana yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat itu sendiri. Menurut Penulis alasan qaul qadim adalah bahwa: air dan tanah sebagai syarat untuk berwudhu (suci dari hadats), maka tidak syah shalat kalau tidak dipenuhi syaratnya. Dengan demikian shalat yang tidak memenuhi syaratnya hanya sia-sia saja. Sedangkan alasan qaul jadid menurut Penulis adalah bahwa: bersuci dari hadats memang benar sebagai salah satu syarat shalat, akan tetapi ketidak mampuan mendapatkan air dan tanah tidak bisa menghilangkan kewajiban shalat. Syarat berwudlu itu adalah bagian dari kebersihan jasmani, sedangkan rohani kita juga dituntut untuk dibersihkan dengan cara melaksanakan perintah Allah berupa shalat. Oleh karena itu ketika air atau tanah telah didapatkan, maka harus mengulangi shalatnya, untuk menyempurnakan kebersihannya, yaitu kebersihan rohani dan jasmani. Alasan lain yang menguatkan qaul jadid adalah bisa diqiaskan dengan perintah shalat itu sendiri. Seperti telah diakui bahwa berdiri dalam shalat itu wajib hukumnya secara mutlak, tetapi walau demikian Allah memberikan rukhsoh (keringanan) kepada orang yang tidak mampu berdiri untuk melaksanakan shalat. Ketika orang itu tidak mampu berdiri, maka shalatlah dalam keadaan berbaring, seandainya berbaringpun tidak mampu, maka shalatlah dengan gerakan lisan (isyarat). Disini sudah jelas bahwa tidak mampunya seseorang untuk melaksanakan salah satu rukun sholat seperti berdiri, tidak menggugurkan kewajibannya untuk melaksanakan shalat, tetapi shalat itu tetap saja wajib dilaksanakan sekalipun dengan isyarat. Dengan demikian ketiadaan air dan tanah tidak menghilangkan perintah wajib shalat, seperti ketidak mampuan berdiri tidak menghilangkan perintah wajib shalat. Disamping itu alasan lain bahwa shalat dalam keadaan tidak mempunyai wudlu (karena tidak ada air dan tanah), bisa juga diartikan sebagai penghormatan kepada waktu. Ada beberapa pendapat para fakar yang menguatkan fatwa qaul jadid seperti tersebut di bawah ini, diantaranya : - Imam Nawawi Al-Banthani menerangkan : اــء#ری-ـ اـ7 ة و یـ_ـ أOـ6 اa وـ.ـP وا ذ ا د + a اـW&ـf ـ#ـری-ـ ـ اC ـ&ضM ا.ـ&اب ﺹـ:وا ـ هـ7اـ د هـ ـ و)ـد ا Artinya: Apabila tiba waktu shalat, tetapi tidak didapatinya alat untuk bersuci, baik itu air maupun tanah, maka shalatlah dalam keadaan tidak mempunyai wudlu, untuk menghormati waktu dan ulangi shalatnya ketika telah mendapatkan salah satu dari ke duanya. - Syihabuddin Qulyuby menerangkan sebagai berikut: 14 ـ7ـ واC Q ـع4ىC سIf آ$&ﺕ8 ی_ـ ء و#و ویـ;ــa اـW&ـf ـ&ضM اـ3ـ6 ا_ـ ی ان ی3C cـ .ـ هـ7ا ذ ا او)ـ ا Artinya: Barang siapa yang tidak mendapatkan air dan tanah, seumpama orang yang terkurung dalam ruangan, yang di dalamnya tidak ada air dan tanah. Maka menurut qaul jadid shalatlah untuk menghormati waktu dan ulangi ketika telah mendapatkan salah satu dari keduanya. - Yahya Zakariya juga menerangkan: ـ7ــ واC Q .ـf$ سIـf آ#ری-ـ&ب ا: اء واC 3و . هـ7 وی;ــ ا ذ ا و)ـ اa اـW&وf 36 ان یـ Artinya: Dan bagi orang yang tidak mendapatkan air dan tanah, untuk berwudlu, seperti orang yang terkurung yang di dalamnya tidak didapati salah satu alat untuk berwudlu, maka shalatlah untuk menghormati waktu dan ulangi apabila telah mendapatkan salah satu alat bersuci tersebut. Dari pendapat para ulama tersebut di atas, pada intinya bahwa sebagian besar ulama Syafi’iyah sepakat, bahwa orang yang tidak mendapatkan air dan tanah ketika datang waktu shalat, hendaklah orang tersebut melaksanakan shalat apa adanya sebagai penghormatan atas waktu dan ulangi shalatnya ketika telah mendapatkan air atau tanah. Pendapat para ulama tersebut di atas, semakin memperkuat analisa Penulis, bahwa fatwa qaul jadid Imam Syafi’i tentang melaksanakan shalat dalam keadaan tidak ada air dan tidak ada tanah yang harus didahulukan dari pada pendapat qaul qadim, karena qaul jadid lebih rasionil dari pada qaul qadim. 4. Tentang Taswib Pada Shalat Shubuh. W;f;ـ ا$ وهان ی=ل. [یـY:ـ اC زادpـI6 اذ ان ا3C ـن آنC .ى_ـ یC J& وآ.# اـم " &ﺕ#&ـP ةO6ة " اO6ا Artinya: Dalam qaul Qadim, apabila pada azan Shubuh, maka ikuti dengan taswib, yang diucapkan setelah kata Hayya ‘alasholah, yaitu dengan kata “Ash-Sholatu khairun Minan-Naom“ dua kali. Sedangkan dalam qaul Jadid dilarang. Dalam masalah taswib, terjadi perselisihan dan perbedaan antara qaul qadim dengan qaul jadid. Pada qaul qadim taswib disunatkan, sedangkan pada qaul jadid dilarang melakukan taswib. Adanya perselisihan dan perbedaan tersebut perlu dicari penyelesaiannya, mana yang harus didahulukan pengunaannya antara qaul dengan qaul jadid. qadim Oleh karena itu Penulis akan mencoba untuk meneliti dan menganalisa lebih lanjut tentang dalil-dalil yang digunakan oleh kedua fatwa tersebut. Ismail Al-Kahlani mengatakan : ذ نq ا ذ ا ل اWـj ا# ل2 اB4 رQ أﻥـ# WیـcP #$8و 15 #$ ـ اff اـم ﺹ#&P ةO6ح ل اOـM ا3;ـى7 &_ـMىC ةO6 اــم اـ#&ــP ةO6ـء اـj اـWى&ویـC و. 3Iـjا .pI6 اـ# ول8ذ ن ا8ىC اــم# &ـP Artinya: Dari Ibnu Huzaimah dari Anas RA. Ia talah berkata “termasuk sunnah yaitu apabila seseorang Muadzin berkata pada ‘Alash Shalah, dilanjutkan dengan adzan subuh dengan kata Hayya kata “Ash-Shalatu khairun Minan Naumi”.Ibnu Subky telah menshahihkan hadits tersebut di atas, dalam riwayat Nasa’ i bahwa “Ash-Shalatu khairun minan-naumi” pada adzan subuh yang pertama. Muhammad Syatha Dimyati menerangkan : ةO6 ا,#:;ـf;ـ ا$ وه ا ن ی=ـلpIذ ان ﺹs [یـY ﺕ#ـ0و &ــP ةO6 اpI6 ا ذا ن ـ8O$ انp ﺹ#I اـم &ﺕ#&P .pI6 Aذ یــd:ىC ;)ـ ا0 و2=ل ﺹىC , اـم# Artinya: Sunnat Taswib pada adzan shubuh sesudah kata “ Hayya alataini‘dengan kata “ Ash-Shalatu Khairun Minan Naomi ” sebanyak dua kali sebagaimana yang telah menjadi shahih ketika Bilal adzan pada shalat shubuh dengan kata-kata “Ash-Shalatu Khairun Minan Naomi”. Kemudian Rasul Saw, bersabda: lakukanlah seperti itu jika engkau adzan pada shalat shubuh. Sedangkan Imam Syafi’i sendiri menerangkan sebagai berikut: # Aـfـ ورة یf $ن ا8 ـ&هL8 وpI6ىC [ـیY:ـ[ ا7ا8و ذا ن8 ا# یـ دةc اJ&آـC [ـیY:d$& اﻥ ا0 ـ و2ى6ىIا ـی[ وهY: اـpI6 ا ذ ا ن ا# یـcى= ی یC ول.[ـیY: اJ&واآ 2ل ا0ذ ن رq ل ـO$ # ـJ وروا,# ا ـم &ﺕـ#&P ةO6ا 3ﻥc اـJ7 ىt ا اt وهـ3=ـI ـ&اج اj ل ا,ـ0 و2ﺹى .ـى:ـM واـ.ىـ;ــC ــ: اـ=ـ ی وهاـ;ـ#ـ Artinya: Saya tidak menyukai taswib dalam adzan shubuh dan yang lainnya, karena Abu Mahdurah tidak pernah meriwayatkan dari Nabi Saw, diperintah untuk bertaswib. Oleh karena itu saya membenci nambah dalam adzan subuh bahwa ia menambah- dan juga membenci taswib. Menurut qaul qadim bahwa pada adzan subuh ditambah dengan taswib yaitu:“Ash-sholatu khairun Minan Naumi” dua kali. Diriwayatkan dari Bilal,seorang tukang adzan pada masa Nabi Saw. berkata Sirajul Bulqiny, sebagaimana yang telah 16 diriwayatkan oleh Muzani dari kaul qadim, yang menjadi pegangan dan fatwa dalam beramal. Dari pendapat ulama tersebut di atas, sebenarnya qaul qadim dilandasi dengan hadits-hadits yang shahih dan masyhur, seperti pendapat Al-Kahlani mengambil hadits dari Abu Hujaimah dan dari Anas, kedua Perawi ini termasuk orang yang tsiqoq, dlabit, jujur dan terpercaya. Begitu juga pendapat Saththa Dimyathi yang melandasi dengan hadits yang sama, meskipun Dia tidak menerangkan dari mana hadits tersebut serta siapa perawi haditsnya. Walaupun demikian karena matan hadits tersebut sama dengan haditshadits lain, maka dengan sendirinya hadits tersebut termasuk hadits masyhur. Lain halnya dengan pendapat Imam Syafi’i dalam qaul jadidnya yang menolak menggunakan taswib pada adzan subuh, dengan alasan karena Nabi tidak memerintahkan kepada Abu Mahdurah untuk melakukan taswib. Sebenarnya fatwa Imam Syafi’i dalam qaul qadim telah dijelaskan oleh Muridnya yang bernama Al-Mazani, yang menerangkan bahwa taswib pada shubuh ada dasarnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Bilal, seorang tukang adzan pada jaman Rasulullah Saw, menurut Al-Mazani pendapat inilah yang lebih kuat. Untuk lebih memperjelas permasalahan antara qaul qadim dengan qaul jadid dan yang mana yang lebih sesuai dengan keadaan masyarakat itu sendiri, maka perlu juga didengar keterangan ulama lainnya, seperti di bawah ini: Syihabuddin Qulyuby menerangkan : cـP ةO6 ا#ـ:;fـ;ـ ا$ وه ان ی=لpI6ىC [یY: ا#ـjوی . ـد )ـ0$ J&ـLى ا ؤ د و$ اZ یfىC J رد# ام &ﺕـ# Artinya: Disunatkan Taswib pada shalat shubuh, yaitu dengan kata-kata“Ash sholatu khairun minan naum, setelah Hayya ‘Alataini” sebanyak dua kali karena ada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga riwayat lainnya dengan sanad yang baik. Ibnu Rusydi juga menerangkan : اـم# &P ةO6 اpI6 ة اO6ىC ذ نq ـل ا# اMـ:ـPوا ـC A ا ﻥ یـ=ـ ل ذ3 هـ[ ا_ر اtـC ؟8 ا مC ی=ـل.ه . Wــﻥـj ذا ن ا8 ا# Qﻥ ـ8 ی=ـل8 &ون انPول ا Artinya: Para Ulama berbeda pendapat tentang perkataan adzan pada shalat shubuh, yaitu masalah “ Asholatu Khairun Minan Naomi”, apakah itu ada dasarnya atau tidak ada dasarnya. ? Jumhur ulama berpendapat bahwa taswib pada shalat subuh ada dasarnya, sedangkan pendapat yanglainnya bahwa taswib bukan termasuk bagian adzan yang disunatkan. Pada intinya fatwa Imam Syafi’i dalam qaul jadid membenci dan melarang untuk mengunakan taswib, tetapi disini Penulis tidak menemukan adanya hadits yang secara jelas melarang untuk taswib. Sedangkan menurut qaul qadim pada adzan shubuh 17 disunatkan melakukan taswib, hal ini telah banyak Hadits Nabi Saw yang menerangkan taswib, seperti hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Turmudzi, Ibnu Majah, Ahmad dan Nasa’i, semuanya meriwayatkan tentang hadits taswib. Bahkan jumhur Ulama sepakat menyatakan bahwa taswib itu disunatkan. Menurut analisa Penulis, alasan (dalil) qaul qadim lebih kuat dari pada qaul jadid, karena qaul qadim didukung oleh sebagian besar ulama. Karena didukung oleh sebagian besar ulama, maka sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang menerangkan “ AlMusbitu Muqaddamun ‘Alan Nafii” Artinya : yang menetapkan (orang Banyak) harus didahulukan dari pada orang yang meniadakan (orang sedikit). Disamping itu qaul kadim lebih sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia, karena diseluruh mesjid di Indonesia selalu menggunakan taswib ketika adzan shubuh tiba. Dengan demikian qaul qadim masih relevan dengan keadan masyarakat itu sendiri, oleh karennya tidak berlaku kata jadid menghapus kata qadim. Demikianlah beberapa sampel yang dapat Penulis kemukakan, tentang adanya perbedaan dan perselisihan antara qaul qadim dan qaul jadid. Sebenarnya banyak sekali tentang adanya perbedaan dan perselishan antara qaul qadim dengan qaul jadid, tetapi dengan beberapa sampel tersebut di atas, kiranya bisa mewakili kepada sampel-sampel yang lainnya. Karena pada dasarnya dalam pembahasan ini, ingin mengetahui apakah benar bahwa qaul qadim telah dihapus oleh qaul jadid. Ternyata setelah diteliti masih banyak qaul qadim yang dalilnya lebih kuat dari pada qaul jadid. Dari empat sampel yang diteliti oleh Penulis, terdapat dua sampel yang menyatakan qaul qadim dalilnya lebih kuat dari pada qaul jadid dan dua sampel lagi yang menyatakan dalil qaul jadid lebih kuat. Dengan demikian berapapun sampel yang dibahas, hasilnya akan tetap sama. Dari empat kasus/sampel yang diteliti oleh Penulis, tidak semua dalil qaul qadim dihapus oleh qaul jadid, karena setelah diteliti dan dianalisa melalui beberapa sampel, ternyata masih banyak dalil qaul qadim yang masih relevan dan lebih kuat dalilnya dibanding dengan kaul jadid. Oleh karena menurut pandangan Penulis jika ditemukan adanya perbeda-an antara qaul qadim dengan qaul jadid, harus diadakan penelitian terlebih dahulu, kemudian dari kedua dalil itu dibandingkan mana yang lebih kuat dan lebih maslahat bagi umat manusia. Hal ini dilakukan sebagai pengecualian terhadap ketentuan umum tentang keshahihan qaul jadid yang telah diakui secara luas. Menurut pandangn Penulis, teore yang paling tepat utuk meninjau kembali qaul qadim sebagai dalil yang lebih kuat/shahih dari pada qaul jadid adalah melalui metode Tarjih. Dengan metode ini kita tidak terpaku lagi dengan kaidah yang menerangkan “ apabila terjadi pertentangan antara qaul qadim dengan qaul jadid, maka dahulukan qaul jadid, karena qaul qadim telah dinasakh”. Metode tarjih dilakukan jika menemukan ada indikasi bahwa dalil qaul qadim lebih shahih/kuat dan lebih maslahat bagi umat manusia. Dorongan untuk melakukan tarjih sebenarnya telah diucapkan oleh Imam Syafi’i sendiri kepada murid-muridnya, seperti kata-kata beliau “ Jika hadits itu shahih, maka itulah maj 18 habku”. Sedangkan hadits yang shahih itu sendiri terdapat dalam qaul qadim dan qaul jadid. Seandainya Imam Syafi’i ditakdirkan dengan umur panjang dan bepindah pindah dari satu negara ke negara lainnya, Penulis yakin akan banyak fatwa Imam Syafi’i yang berbeda antara qaul qadim dengan qaul jadid, kemungkinan besar Imam Syafi’i akan mengeluarkan fatwa yang lebih baru lagi dari qaul jadid, dan itu akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan tempat dan jaman. Imam Syafi’i memberi kebebasan kepada murid-muridnya untuk berijtihad, serta tidak terikat dengan pendapat guru-gurunya, apalagi jika pendapat gurunya itu tidak sesuai dengan keyakinannya. Pandangan Imam Syafi’i tersebut membuka cakrawala baru bagi pembentukan hukum Islam yang selalu hidup dan berkembang sesuai dengan jamannya dan sesuai pula dengan adat istiadat bangsa itu sendiri. Dari permasalahan yang ditemukan oleh Penulis, tentang adanya perbedaan dan perselisihan antara qaul qadim dan qaul jadid, kebanyakan menyangkut masalah ibadah, mu’amalah dan munakahat, dari ke tiga masalah tersebut yang paling banyak adalah menyangkut masalah ibadah. Dengan demikian rasanya tidak salah kalau Penulis berasumsi, bahwa Imam Syafi’i begitu kreatif mengadakan perubahan-perubahan hukum yang menyangkut masalah ibadah, padahal yang menyangkut masalah ibadah kebanyakan ulama masih kaku dan terikat dengan dalil-dalil yang ada, sekalipun dalil-dalil itu bersifat umum, seolah-olah mengadakan perubahan dalam masalah ibadah adalah bid’ah, padahal itu telah dilakukan oleh Imam Syafi’i. Mungkin menurut Penulis tidak menaruh besar terhadap perubahan-perubahan hukum yang menyangkut ibadah seperti yang dilakukan oleh Imam Syafi’i, tetapi ada yang lebih penting dan lebih maslahat bagi kehidupan manusia adalah mengadakan perubahan hukum dalam bidang mua’malah. Dengan demikian pandangan Imam Syafi’i dalam qaul qadim dan qaul jadid, sebagai wacana bagi kita untuk mengadakan perubahan-perubahan hukum, terutama hukum mu’amalah, yang selama ini masih tetap berpegang kepada fiqh temporer, yang kemungkinan besar sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat sekarang. D. IMPLIKASI QAUL QADIN DAN QAUL JADID TERHADAP PERUBAHAN HUKUM ISLAM Seperti telah diuraikan di atas, tampak dengan jelas bahwa hukum dalam mazhab Imam Syafi’i bersifat dinamis, hal itu bisa dibuktikan dengan adanya beberapa fatwa Imam Syafi’i yang dipengaruhi oleh berbagai situasi, kondisi dan keadaan. Sejak masih berada di Hijaz (Makkah dan Madinah) ketika usia Imam Syafi’i masih muda telah mengeluarkan beberapa fatwa tentang hukum, fatwa tersebut telah bertentangan dengan gurunya di Hijaz (Imam Malik bin Annas) fatwa tersebut oleh Penulis disebut dengan pra qaul qadim, kemudian setelah tinggal di Bagdad Imam Syafi’i mengeluarkan fatwa pula yang disebut dengan qaul qadim, dan terakhir setelah tinggal di Mesir sampai wafatnya telah banyak mengeluarkan fatwa yang disebut dengan qaul jadid. Menurut pandangan 19 Imam Syafi’i kebenaran hukum yang ditemukan hasil ijtihad itu bersifat relatif (zhanny) bukan mutlak, maka tetap terbuka bagi pengkajian dan kemungkinan perubahan. Kemungkinan adanya perubahan tersebut bisa dilihat dari hal-hal sebagai berikut: 1. Praktik Imam Syafi’i sendiri yang dalam waktu singkat telah mengemukakan beberapa fatwa, tidak hanya qaul qadim dan qaul jadid, tetapi ada beberapa fatwa yang dikeluarkan sebelum qaul qadim dan setelah qaul jadid. 2. Larangan taqlid serta anjuran ijtihad yang ditekankan oleh Imam Syafi’i terhadap murid-muridnya, termasuk arahan dan anjuran agar memeriksa kembali hasil fatwanya, serta meninggalkan fatwanya bila tidak sesuai dengan hadits yang shahih. 3. Penyusunan dan penataan kaidah-kaidah ushul fiqh sebagai pedoman dalam melakukan ijtihad, kenyataannya kaidah-kaidah tesebut mengalami perkembangan melalui kajian lebih lanjut oleh para ulama As- Syafi’iyah. 4. Praktik para murid Imam Syafi’i yang senantiasa melakukan ijttihad, berupa penelitian ulang terhadap fatwa Imam Syafi’i sendiri dan penerapan hukum terhadap masalah-masalah baru. 5. Kenyataan adanya perbedaan dan saling koreksi yang berkelanjutan di kalangan ulama Syafi’iyah dalam kegiatan ijtihad, sebagian ulama Syafi’iyah tidak membenarkan adanya taqlid kepada mujtahid yang telah wafat. Dari fakta-fakta tersebut di atas, dapat diratik suatu kesimpulan bahwa mazhab Imam Syafi’i menghendaki agar hukum yang difatwakan harus selalu baru. Setiap kejadian, situasi, kondisi memerlukan fatwa dan menuntut untuk berijtihad. Ijtihad terdahulu yang dilakukan sehubungan dengan kasus yang pernah terjadi, pada prinsipnya tidak berlaku untuk kasus serupa bila terjadi pada waktu atau kondisi yang berbeda, terutama bila melihat adanya hal-hal yang mengharuskan peralihan fatwa. Kodifikasi hukum Islam dengan alasan untuk mendapatkan kesatuan dan kepastian hukum, sebenarnya kurang sesuai dengan prinsip mazhab Imam Syafi’i. Prinsipnya bahwa setiap kejadian menuntut ijtihad tersendiri dan ini tidak sejalan dengan kodifikasi hukum, bahkan mengekang kebebasan hakim untuk berijtihad. Menurut prinsip mazhab Imam Syafi’i “seorang hakim haruslah mujtahid dan setiap mujtahid tidak boleh bertaqlid”. Jadi hakim tidak boleh mengikuti pendapat orang lain, termasuk pendapat yang telah dikodifikasi. Akan tetapi, karena masalah ini berada dalam lingkup AlSiyasah, maka pengaturannya jelas menjadi wewenang penguasa. Tindakan penguasa harus ditunjukan kepada kemaslahatan umat, bila kodifikasi sudah dianggap sebagai kemaslahatan, penguasa baleh melakukannya walaupun tidak sesuai dengan pendirian mazhab. Kodifikasi oleh penguasa tidak dapat ditentang demi kewibawaan pemerintah, masalah khilafiyah tidak berlaku terhadap tindakan penguasa, bahkan keputusan dan tindakan penguasa dapat mengangkatkan khilaf yang ada. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, mazhab Imam Syafi’i, dengan semangat ijtihad dan dinamika yang dimilikinya sebagaimana terlihat pada peralihan dari 20 satu qaul ke qaul lainnya serta perkembangan mazhab ini selanjutnya, tidak mungkin menentang, bahkan sebaliknya sangat mendukung upaya pembaharuan hukum dengan ijtihad secara berkelanjutan. Dengan ketentuan ijtihad dilakukan dengan benar dan tidak meninggalkan kaidah-kaidah yang berlaku, supaya hukum yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan sebagai hukum Islam. Kaidah-kaidah ushul fiqh yang diciptakan oleh Imam Syafi’i mempunyai pengertian yang cukup luas, diantaranya dalam pembahasan qiyas. Sehingga berbagai dalil yang disebut-sebut pada mazhab lainnya, semisal Istihsan, maslahat mursalah dan lain sebagainya dalam batas-batas tertentu telah tercakup di dalamnya. Oleh karena itu dengan menggunakan metode istinbath As-Syafi’i, seorang mujtahid akan tetap mempunyai kebebasan berijtihad yang cukup luas dalam merespons dan memberikan jawaban atas setiap masalah yang terjadi dalam perkembangan jaman. Perkembangan zaman yang semakin modern, kebudayaan manusia yang semakin maju, akan senatiasa menuntut respons hukum terhadap berbagai perubahan sosial dan budaya. Kebutuhan akan ijtihad akan terus berkembang, bahkan cendrung semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kekayaan dan perbendahraan fawa Imam Syafi’i mungkin saja tidak cukup lagi untuk merespons perubahan-perubahan tersebut, sehingga kebutuhan untuk ijtihad semakin meningkat. Mungkin sebelumnya ijtihad muqayyad dan tarjih sudah memadai, akan tetapi pada gilirannya hajat masyarakat akan menuntut ijtihad mutlak atau ijtihad mutlak mustaqil. Dengan mengamati perkembangan kebudayaan dam kemajuan zaman, telah nampak bahwa perubahan fatwa Imam Syafi’i dari satu qaul ke qaul lainya tidak hanya terjadi pada fatwa-fatwa hukum sebagai hasil ijtihad, melainkan juga terjadi pada sebagian kaidah-kaidah ijtihad itu sendiri. Koreksi dari Ashhab ( teman-teman Syafi’i) terhadap pendapatnya tampak jelas meliputi ke dua bidang. Perbedaan pendapat dan saling koreksi dalam kajian ushul fiqh dikalangan syafi’iyah tidak kalah ramainya dengan yang terjadi pada kajian fatwa mazhab. Hal ini dapat dijadikan sebagai modal dasar untuk melaukukan perubahan-perubahan hukum yang disesuaikan dengan keadaan, situasi, zaman dan kondisi masyarakat setempat. Sepanjang sejaran, perkembangan ilmu pengetahuan selalu terkait dan saling mempengaruhi dengan keadaan politik, sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. Ketika kekuatan politik umat Islam mengalami disintegrasi pada abad pertengahan, kegiatan ilmiyah termasuk ijtihad tidak lepas dari pengaruhnya. Semangat ijthad melemah dan sikap bertaqlid semakin meluas, bahkan termasuk dikalangan ulama sendiri. sejak abad IV hijriyah tidak ada lagi ulama yang mengaku sebagai mujtahid mutlak mustaqil (lepas dari keterikatan pendapat orang). Pada waktu itu kegiatan ijtihad hanya terbatas pada dalam mazhab anutan masing-masing. Meskipun demikian banyak ulama usuhl fiqh yang hidup pada masa itu menyatakan bahwa keberadaan mujtahid mutlak merupakan fardu kifayah. Dengan demikian apabila suatu masa tidak ada mujtahid mutlak, berarti umat ini telah gagal melaksanakan salah satu kewajibannya. 21 Sudah dapat dipastikan, bahwa untuk mencapai tingkat ijtihad mutlak itu tidaklah sederhana, karena kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi cukup berat. Akan tetapi itu akan terasa lebih mudah dipelajari bila dibandingkan dengan keadaankeadaan pada masa imam-imam mujtahid yang hidup pada abad ke dua dan ke tiga hijriyah. Alasan-alasan lain yang memudahkan adalah bahwa ilmu-ilmu mendukung yang untuk berijtihad telah ada, seperti tafsir, hadits, ushul fiqh dan lain sebagainya. Dengan demikian banyaknya kemudahan yang dapat menunjang pendidikan pada zaman modern ini, dapat diharapkan pencapaian tingkat ijtihad itu akan menjadi lebih mudah lagi dibandingkan dengan masa-masa kemunduran Islam. Sehingga hukum Islam tetap berkembang sesuai dengan berkembangnya, waktu, tempat dan kebudayaan masnusia itu sendiri, dan sekaligus kemurnian Islam tetap terjaga. E. KESIMPULAN Metodologi istinbat hukum melalui qiyas, adalah sebagai upaya ijitihad Imam Syafi’i dalam menghadapi peristiwa-peristiwa baru yang tidak terdapat dalam AlQur’an dan Sunnah. Peristiwa-peristiwa baru tersebut timbul karena berkembangnya beradaban kebudayaan manusiadan, faktor perbedaan alam, sehingga hukum Islam dituntut untuk memecahkan masalah-masalah baru yang tidak terdapat adalam AlQur’an dan As-Sunah. Sesuai dengan kaidah yang berbunyi “Hukum itu selalu berubah, sesuai dengan perubahan tempat dan jaman”. Perubahan fatwa Imam Syafi’i dari qaul qadim ke qaul jadid dapat terjadi, karena menurut Imam Syafi’i setiap kasus menuntut untuk berijtihad tersendiri, dan fatwa harus senantiasa baru sesuai dengan hasil ijtihad terakhir serta tidak terikat dengan fatwa terdahulu. Perubahan fatwa Imam Syafi’i dari qaul qadim ke qaul jadid, karena dilatar belakangi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor geografis, faktor kebudayaan dan adat istiadat, faktor ilmu pengetahuan, faktor metodologi dan faktor tuntutan dari murid Imam Syafi’i. Pengaruh dari faktor-faktor tersebut di atas, jelas tampak pada keragaman masalah yang dibahasnya, setiap kali menghadapi kasus-kasus yang aktual, Imam Syafi’i melakukan ijtihad dengan mempergunakan dalil, kaidah dan sisi pandang yang paling tepat. Dari beberapa sampel yang dianalisa antara fatwa qaul qadim dengan qaul jadid, ternyata telah ditemukan ada beberapa fatwa qaul qadim yang dalilnya lebih kuat dan lebih maslahat bila dibandingkan dengan qaul jadid. Untuk mengetahui adanya dalil qaul qadim yang lebih kuat/lebih shahih bila dibandingkan dengan qaul jadid adalah melalui metode tarjih. Gerakan pembaharuan hukum Islam pada masa modern selalu membangkitkan semangat ijtihad , undang-undang menyerukan penataan kembali hukum Islam, sesuai dengan serta menyusun kemajuan zaman. Mazhab Imam Syafi’i sangat mendukung dalam pembaharuan hukum. Dalam pandangan Imam Syafi’i, kebenaran 22 fatwa diukur dengan kekuatan dalil yang mendukungnya. Pendapat terdahulu tentang suatu kasus tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap kasus berikutnya. Dalam menghadapi perbendaharaan permasalah hukum, fatwa-fatwa yang ada pada mazhab Imam Syafi’i layak ditelusiri dan diteliti ulang dengan menggunakan kaidah-kaidah ijtihad yang telah dirumuskannya. Untuk kasus-kasus baru yang belum terjangkau oleh kajian mazhab, kaidah-kaidah tesebut dapat dipedomani dalam penanganan dalil-dalil terkait, melalui ijtihad jama’i. Dengan demikian, dinamika hukum dalam mazhab Imam Syafi’i sangatlah relevan dengan upaya pembaharuan hukum Islam pada masyarakat modern yang dinamis. Dilihat dari teori hukum “ Lex Posterior Derogat Legi Priori”, artinya hukum yang datang terakhir harus didahulukan/diberlakukan dari pada hukum yang datang lebih dahulu. Begitu juga dengan teori nasakh mansukh yang merupakan teori yang diakui oleh Imam Syafi’i, yang menyatakan ayat yang datang terakhir dapat menghapus ayat yang datang lebih dahulu. Dengan demikian semakin memperkuat kesimpulan Penulis, bahwa Imam Syafi’i selalu berubah-ubah dalam berijtihad, karena imam Syafi’i selalu mendahulukan kemaslahatan hukum bagi masyarakat dan kondisi masyarata setempat. Hal ini dapat dibuktikan bahwa qaul qadimnya imam Syafi’i masih ada yang relevan dengan jaman sekarang sekalipun telah ada qaul jadidnya. Hal inilah menurut Penulis pemikiran-pemikiran imam Syafi’i yang sangan brilian untuk menjadi penggerak bagi kita semua dalam menggali hukum melalui ijtihad.