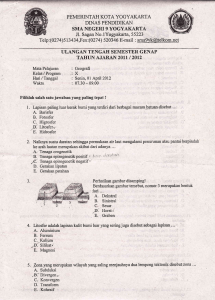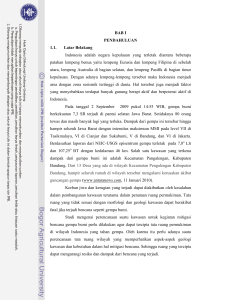bab i pendahuluan
advertisement

1 BAB I PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang Ionosfer merupakan salah satu lapisan di atmosfer bumi yang memiliki beragam manfaat bagi kehidupan makhluk hidup. Banyak penelitian yang telah dilakukan terhadap ionosfer untuk menggali lebih dalam manfaatnya. Salah satunya ialah dengan meneliti kerapatan elektron di ionosfer atau dikenal dengan istilah Total Electron Content (TEC). TEC menyatakan jumlah elektron dalam silinder dengan penampang seluas 1 m2 dengan panjang antara satelit Global Navigation Satellite System (GNSS) dan receivernya (Astra dan Pudja, 2009). Penelitian terhadap TEC ionosfer memiliki beberapa manfaat salah satunya untuk mendeteksi pertanda dan dampak bencana gempa bumi dengan magnitude gempa lebih dari 6 SR (Subakti, dkk., 2008). Gempa bumi dengan magnitude sebesar ini mampu menyebabkan anomali di ionosfer. Anomali ini dideteksi dengan cara menganalisis variasi nilai TEC di lokasi terjadinya gempa bumi tersebut (Liu, dkk., 2001). Pada beberapa kasus gempa bumi yang ada sebelumnya, penerapan analisis TEC ini telah banyak dilakukan dengan menggunakan analisis terhadap anomali variasi nilai TEC harian, misalnya pada gempa bumi dengan magnitude 9,0 SR yang terjadi di pesisir barat Sumatera Utara, Indonesia pada 26 Desember 2004. Pada kasus ini terjadi anomali pada variasi nilai TEC harian di stasiun SAMP, stasiun IISC, dan stasiun BAKO pada 2 s.d 7 hari gempa Aceh itu terjadi (Saroso, 2010). Pada penelitian ini, dilakukan analisis variasi nilai TEC harian di lokasi terjadinya gempa dengan magnitude 7,3 SR di Laut Maluku, pada 15 November 2014. Pengamatan variasi TEC dilakukan dari lima stasiun pengamatan GNSS. Kelima stasiun tersebut terdiri atas satu stasiun IGS di Kota Bitung (Provinsi Sulawesi Utara) dan empat stasiun lainnya adalah CORS yang terdapat di Kota Bitung (Provinsi Sulawesi Utara), Ternate (Provinsi Maluku Utara), Biak (Provinsi Papua Barat), dan Sorong (Provinsi Papua Barat). Pengamatan ini dilakukan sejak 25 hari sebelum sampai dengan 30 hari sesudah terjadinya gempa tersebut, atau lebih tepatnya sejak tanggal 21 Oktober hingga 16 Desember 2014. 1 2 I.2. Rumusan Masalah Gempa bumi yang terjadi di Laut Maluku pada 15 November 2014 merupakan gempa dengan magnitude 7.3 SR. Pada kekuatan gempa di atas 6 SR ini sangat dimungkinkan terjadi anomali TEC. Namun saat ini belum diketahui apakah terjadi anomali ionosfer sebelum gempa bumi terjadi. Untuk itu, perlu dilakukan analisis terhadap variasi nilai TEC harian beberapa hari sebelum terjadinya gempa tersebut. Berdasarkan data pengamatan GNSS pada satu stasiun IGS dan empat stasiun CORS di sekitar lokasi gempa bumi. I.3. Pertanyaan Penelitian Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah : 1. Apakah terdapat anomali nilai TEC sebelum terjadi gempa bumi di Laut Maluku pada 15 November 2014 ? 2. Apakah anomali nilai TEC yang terjadi merupakan prekursor gempa bumi di Laut Maluku pada 15 November 2014 ? I.4. Cakupan Penelitian Cakupan penelitian yang dibahas dalam penelitian ini adalah : 1. Wilayah penelitian adalah di sekitar lokasi terjadinya gempa bumi di Laut Maluku pada 15 November 2014. 2. Data yang digunakan adalah data pengukuran GNSS pada lima stasiun pengamatan GNSS kontinyu. Kelima stasiun tersebut terdiri atas satu stasiun IGS di Kota Bitung (BTNG) dan empat lainnya adalah stasiun CORS yang terdapat di Kota Bitung (CBIT), Kota Biak (CBIK), Ternate (CTER), dan Kota Sorong (CSOR). 3. Analisis anomali nilai TEC harian dilakukan sejak 25 hari sebelum sampai dengan 30 hari sesudah terjadinya gempa bumi tersebut. 3 I.5. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan nilai TEC di ionosfer untuk mengetahui apakah terdapat anomali sebelum 15 November 2014 di sekitar Laut Maluku, dan mengetahui apakah anomali yang terjadi merupakan prekursor gempa bumi di Laut Maluku. I.6. Manfaat Penelitian Penelitian ini bermanfaat untuk menghasilkan informasi tentang keterkaitan antara bencana gempa bumi dengan keadaan atmosfer sebelum gempa bumi itu terjadi. Selanjutnya hubungan keterkaitan tersebut dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam penelitian di masa mendatang. I.7. Tinjauan Pustaka Saroso (2010) dalam makalahnya yang berjudul “Ionosfer Untuk Komunikasi Radio, Navigasi, dan Informasi Mitigasi Gempa” menjelaskan bahwa penelitian terhadap TEC ionosfer dapat dikaitkan dengan terjadinya gempa bumi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh LAPAN, prekursor gempa bumi ditandai berdasarkan anomali TEC berupa penurunan nilai TEC ionosfer. Pada gempa bumi di Sulawesi Utara pada tanggal 4 Mei 2000 dengan kekuatan 7,6 SR dapat diketahui tiga prekursor. Astra dan Pudja (2009) menjelaskan hal yang sama dalam makalahnya yang berjudul “Analisa Vertical Total Electron Content di Ionosfer Daerah Jawa dan Sekitarnya yang Berasosiasi dengan Gempa bumi Yogyakarta 26 Mei 2006 UTC”. Dalam makalah ini dijelaskan bahwa terjadi anomali berupa penurunan jumlah kandungan elektron di ionosfer VTEC beberapa hari sebelum gempa Yogyakarta terjadi, yaitu pada tanggal 18, 20, dan 22 Mei 2006. Subakti, dkk., (2008) dalam makalahnya yang berjudul “Analisis Variasi GPSTEC yang Berhubungan dengan Gempa bumi Besar di Sumatera” menjelaskan bahwa tidak semua gempa berskala besar akan diketahui prekursornya melalui TEC ionosfer. Dari 10 gempa bumi dengan kekuatan yang lebih besar dari 6 SR di Sumatera pada bulan Desember 2004 hingga April 2005, terdapat sembilan gempa bumi yang dapat diketahui prekursornya. 4 Muslim (2015) menjelaskan bahwa prekursor gempa bumi dengan kekuatan lebih dari 8 SR akan lebih efektif dideteksi dengan metode teknik autokorelasi. Telah dibuktikan pada penelitian yang dilakukan terhadap 17 gempa bumi yang terjadi antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2012 di dunia, terdapat 63% prekursor gempa bumi yang terdeteksi. Penelitian ini mengkaji tentang anomali ionosfer yang terjadi beberapa hari sebelum terjadinya gempa bumi di Laut Maluku pada 15 November 2014. Anomali tersebut diamati dengan pengukuran GNSS yang dilakukan di lima stasiun, yaitu satu stasiun IGS di Kota Bitung dan empat stasiun lainnya adalah CORS yang terdapat di Kota Bitung, Ternate Biak, dan Sorong. Teknik Autokorelasi digunakan untuk mengidentifikasi apakah anomali yang terjadi disebabkan oleh gempa bumi tersebut. I.8. Landasan Teori I.8.1 Global Navigation Satellite System (GNSS) GNSS merupakan teknologi yang digunakan untuk menentukan posisi atau lokasi dalam satuan ilmiah di Bumi. Satelit akan mentransmisikan sinyal radio dengan frekuensi tertentu yang berisi data waktu dan posisi yang dapat diambil oleh penerima. Data ini memungkinkan pengguna untuk mengetahui lokasi mereka secara tepat (Huda, 2013). GNSS terdiri dari tiga segmen utama yaitu segmen angkasa, segmen kontrol, dan segmen pemakai. Segmen angkasa terdiri atas satelit-satelit GNSS, yang memancarkan sinyal dalam dua frekuensi. Segmen Kontrol terdiri atas Master Kontrol Station dan beberapa Monitor Station yang tersebar di seluruh dunia, sedangkan segmen pemakai (user segment) terdiri atas pemakai GNSS termasuk alat penerima serta pengolah sinyal dan data GNSS (Abidin, 2000). 1.8.1.1 Perjalanan sinyal GNSS. Secara garis besar, cara kerja GNSS adalah dikirimnya sinyal oleh satelit ke antena penerima. Setiap daerah di bumi minimal terjangkau oleh empat buah satelit. Jumlah ini dibutuhkan untuk mendapatkan posisi antena penerima dalam tiga dimensi. Setiap satelit akan memancarkan sinyal yang akan diterima oleh receiver GNSS. Jarak yang ditempuh oleh sinyal tersebut 5 menyatakan jari-jari lingkaran jangkauan setiap satelit. Kemudian dengan menggunakan prinsip triangulasi maka posisi GNSS di permukaan bumi dapat ditentukan. Dalam perjalanannya dari satelit hingga sampai ke pengamat di permukaan bumi, sinyal GNSS mengalami beberapa gangguan. Abidin (2000) menjelaskan bahwa terdapat sebelas kesalahan dan bias sinyal satelit GNSS, yaitu kesalahan ephemeris (orbit satelit), bias ionosfer, bias troposfer, multipath, ambiguitas fase, cycle slips, selective avaibility (SA), anti spoofing, kesalahan jam satelit dan receiver, pergerakan dari pusat fase antena, dan imaging. Berbagai kesalahan tersebut akan menyebabkan kesalahan pada jarak ukuran dengan GNSS baik pseudorange maupun jarak fase. Oleh sebab itu, bias dan kesalahan tersebut harus diperhitungkan dalam pemrosesan sinyal GNSS untuk keperluan penentuan posisi ataupun parameter lainnya. 1.8.1.2. Sinyal Satelit GNSS. Satelit GNSS memancarkan sinyal ke receiver di bumi. Sinyal GNSS dapat dibagi atas tiga komponen. 1. Sinyal penginformasi jarak (kode). Sinyal ini terdiri dari dua kode Pseudo Random Noise (PRN) yang digunakan sebagai penginformasi jarak, yaitu kode-P(Y) (P : Precise atau Private) dan kode-C/A (C/A : Coarse Acquisition atau Clear Access). Kode-kode ini terdiri dari rangkaian bilangan biner (1 dan 0), yang mempunyai struktur yang unik (tertentu) dan berbeda untuk satiap satelit GNSS. Dengan demikian, receiver GNSS dapat mengamati dan membedakan sinyal-sinyal yang datang dari satelit yang berbeda (Abidin, 2000). Jarak dari pengamat ke satelit dapat ditentukan dengan mengamati kode-P(Y) ataupun kode-C/A. Pengukuran jarak ini mengandung bias terutama yang berasal dari kesalahan antara jam satelit dan receiver GNSS. Jarak yang mempunyai bias ini dinamakan dengan jarak semu (pseudorange), sehingga prinsip dasar dari pengamatan GNSS dapat juga dinamakan dengan pengamatan pseudorange. Pengamatan pseudorange. Dasar pengamatan pseudorange adalah penentuan jarak dari receiver ke satelit melalui pengukuran selisih waktu (Δt), yaitu waktu yang diperlukan oleh kode untuk menempuh jarak dari satelit ke antena receiver. Jarak yang diukur pada pengamatan menggunakan data kode bukanlah 6 jarak yang sebenarnya, melainkan suatu jarak semu yang disebabkan antara lain karena ketidaksinkronan antara jam di satelit dengan jam di receiver. Oleh karena itu, untuk pengukuran yang dilakukan dengan data kode diperoleh persamaan jarak semu (pseudorange). Persamaan pengamatan untuk mencari jarak yang telah dilinierkan dan memperhitungkan semua bias dan noise yang ada pada pseudorange dinyatakan dalam Persamaan (1) berikut ini (Abidin, 2000) : 𝑃 = 𝜌 + 𝑑𝜌 + 𝑑𝑡𝑟𝑜𝑝 + 𝑑𝑖𝑜𝑛𝑖 + (𝑑𝑡 − 𝑑𝑇) + 𝑀𝑃𝑖 + 𝑣𝑃𝑖 ...................... (1) dengan P : jarak pseudorange ρ : jarak geometrik antara pengamat dan satelit, dρ : efek dari bias di ephemeris satelit, dtrop : bias jarak yang disebabkan oleh troposfer, dion : bias jarak yang disebabkan oleh ionosfer, dt : bias jarak karena kesalahan waktu di receiver, dT : bias jarak karena kesalahan waktu di satelit, Mpi : efek dari multipath pseudorange, dan υPi : noise dari pseudorange Pengamatan Carrier Phase. Selain pseudorange, juga terdapat ukuran jarak dengan menggunakan fase sinyal. Pengukuran jarak dengan fase dari pengamat ke satelit bukanlah merupakan jarak absolut, tetapi merupakan jarak yang ambigu. Untuk mengubah data fase menjadi data jarak, maka ambiguitas fase (N) harus ditentukan terlebih dahulu nilainya. Dalam pengamatan carrier phase, jarak antara receiver dan satelit diperoleh dengan cara mengamati selisih fase antara fase sinyal pembawa (L1/L2) yang datang dari satelit dan fase oleh receiver. Pada pengamatan ini, terdapat sejumlah N cycle gelombang yang tidak teramati yang dikenal sebagai cycle ambiguity. Besaran N yang ada akan selalu tetap jumlahnya selama sinyal yang diterima oleh receiver tidak terhalang. Apabila sinyal terhalang maka terjadilah cycle slip dan besaran N harus 7 ditentukan lagi (Abidin, 2000). Persamaan (2) merupakan persamaan jarak fase dengan memperhitungkan pengaruh bias ionosfer, bias toposfer, noise (υp), dan multipath (mp) : 𝐿𝑖 = 𝜌 + 𝑑𝜌 + 𝑑𝑡𝑟𝑜𝑝 + 𝑑𝑖𝑜𝑛𝑖 + (𝑑𝑡 − 𝑑𝑇) − 𝜆𝑖. 𝑁𝑖 + 𝑀𝐶𝑖 + 𝑣𝐶𝑖 ................... (2) dengan Li : pengukuran fase dalam satuan jarak, ρ : jarak geometrik antara pengamat dan satelit, dρ : efek dari bias di ephemeris satelit, dtrop : bias jarak yang disebabkan oleh troposfer, dion : bias jarak yang disebabkan oleh ionosfer, dt : bias jarak karena kesalahan waktu di receiver, dT : bias jarak karena kesalahan waktu di satelit, λi : panjang gelombang sinyal, Ni : ambiguitas fase, MCi : efek dari multipath fase, dan υCi : noise dari fase 2. Sinyal penginformasi posisi satelit (navigation message). Sinyal GNSS juga berisi pesan navigasi yang menginformasikan posisi dan kondisi satelit. Pesan navigasi merupakan sinyal yang ditambahkan pada kode L1 yang memberikan informasi tentang parameter orbit satelit, parameter koreksi ionosfer, UTC, almanak satelit, koreksi jam satelit dan receiver dan status sistem lainnya. Pesan navigasi ini ditentukan oleh segmen sistem kontrol dan dikirimkan ke pengguna menggunakan satelit GNSS (Dana, 1997). 3. Gelombang pembawa (carrier wave). Terdapat dua gelombang pembawa yaitu L1 dan L2. gelombang ini bertugas membawa kode dan pesan navigasi dari satelit ke pengamat. Masing-masing gelombang tersebut memiliki nilai frekuensi masing-masing tergantung pada satelitnya. Misalnya pada GPS, L1 berfrekuensi 1575,42 MHz dan L2 pada GPS berfrekuensi 1227,60 MHz. Gelombang L1 membawa 8 kode biner P(Y) dan C/A beserta pesan navigasi, sedangkan gelombang L2 hanya membawa kode-C/A dan pesan navigasi (Dana, 1997). I.8.2 International GNSS Services (IGS) (IGS, 2015) menjelaskan bahwa International GNSS Service (IGS) merupakan layanan GNSS internasional yang memberikan akses secara terbuka terhadap produkproduk GNSS sejak tahun 1994. Produk-produk dari layanan ini dapat dimanfaatkan untuk aplikasi ilmiah, pendidikan, dan komersial sehingga dapat mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan kepentingan publik Produk-produk yang disediakan oleh IGS meliputi efemeris satelit GNSS, parameter rotasi bumi, koordinat dan kecepatan stasiun pelacakan global, informasi jam satelit dan stasiun pelacakan, perkiraan delay zenith troposfer, dan peta ionosfer global. Selanjutnya produk-produk tersebut dapat dimanfaatkan antara lain untuk pemantauan deformasi bumi, pemantauan rotasi bumi, pemantauan troposfer dan ionosfer, dan penentukan orbit satelit ilmiah, dan beragam aplikasi lainnya. 1.8.2.1. Stasiun IGS. Untuk mendukung misi dan ketersediaan data yang akurat, saat ini IGS memiliki lebih dari 452 stasiun pengamatan yang tersebar di seluruh permukaan bumi. Stasiun- stasiun tersebut mengambil data setiap harinya, dua puluh empat jam secara kontinyu. Gambar I.1 menunjukkan persebaran stasiun pengamatan IGS. Titik-titik hijau menunjukkan lokasi masing-masing stasiun pengamatan IGS. Hampir setiap negara di dunia mempunyai stasiun IGS. Stasiun IGS di Indonesia terdapat di tiga kota, seperti tertera pada Tabel (I.1) berikut ini : Tabel I.1. Lokasi IGS di Indonesia (IGS, 2015) No Nama Stasiun Kota Lintang Bujur Satelit 1 BAKO Cibinong (Jawa Barat) 6,49 LS 106,85 BT GPS dan GLONASS 2 BNOA Benoa (Bali) 8,746 LS 115,21 BT GPS 3 BTNG Bitung (Sulawesi Utara) 1,439 LS 125,19 BT GPS 9 Gambar I. 1 Lokasi persebaran stasiun IGS di permukaan bumi (IGS, 2015) I.8.3 Continuously Operating Reference Station (CORS) CORS merupakan salah satu teknologi berbasis GNSS yang dimanfaatkan untuk berbagai aplikasi terkait penentuan posisi. CORS merupakan jaring kerangka geodetik berupa stasiun pengamatan permanen yang dilengkapi dengan receiver yang dapat menerima sinyal dari satelit GNSS, yang beroperasi secara kontinyu selama dua puluh empat jam (Hutomo, 2010). CORS pertama kali dikembangkan di Amerika Serikat sejak Oktober 2001 oleh The National Geodetic Survey (NGS) yang merupakan bagian dari National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) dan mulai dioperasikan secara kontinyu sejak November 2005 (Snay dan Soler, 2008). Azmi (2012) menerangkan bahwa CORS yang ada di Indonesia dibuat oleh beberapa lembaga misalnya Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). BIG mulai mengembangkan CORS sejak tahun 1996. BIG hingga tahun 2011 telah memiliki 117 stasiun dimana 99 stasiun CORS merupakan stasiun yang dibangun oleh BIG dan 18 stasiun merupakan stasiun hasil kerja sama dengan pemerintah negara Jerman sebagai bagian dari pembangunan proyek Germany Indonesia Tsunami Early Warning System (GITEWS). 10 Sementara BPN, telah memiliki 93 stasiun, dengan komposisi 70 stasiun berada di pulau Jawa dan Bali dan 23 lainnya berada di luar Jawa dan Bali. Pada awal perencanaan pembangunan jaringan CORS tersebut, BPN membagi dua jenis stasiun CORS yaitu stasiun kelas A dan kelas B. Stasiun CORS kelas A milik BPN, dibuat dengan fraksi jarak antar stasiun CORS yaitu 100 s.d. 200 km dan juga stasiun tersebut harus didirikan di atas tanah serta dilengkapi dengan receiver GPS dual-frequency. Untuk stasiun CORS kelas B akan dibuat sebagai perapatan dari stasiun CORS kelas A dengan fraksi jarak 30 s.d. 50 km dan dapat didirikan di atas atap gedung dengan konstruksi yang kuat. CORS milik BPN memiliki fungsi utama untuk mempercepat administrasi pertanahan di Indonesia. I.8.4 Ionosfer 1.8.4.1 Lapisan ionosfer. Janssen (2012) menerangkan ionosfer merupakan salah satu lapisan dalam atmosfer bumi dengan ketinggian antara 50 km hingga 1000 km. Berdasarkan perbedaan molekul-molekul dan atom-atom di dalam atmosfer dan tingkat perbedaan mereka dalam kemampuan menyerap, maka lapisan ionosfer dapat dibagi ke dalam beberapa lapisan. Berikut akan dijelaskan mengenai pembagian keempat lapisan tersebut. 1. Lapisan D Lapisan ini adalah lapisan ionosfer yang paling bawah, yang memiliki puncak ketinggian sekitar 50 km hingga 95 km. Lapisan ini paling sedikit menerima pancaran Extreme Ultra Violet (EUV) sehingga partikel netralnya lebih banyak dari pada partikel yang bermuatan. Kerapatan partikel bermuatan pada lapisan ini merupakan yang paling rendah dibandingkan lapisan lainnya. 2. Lapisan E Lapisan ini merupakan lapisan ionosfer yang tipis dengan tingkat kerapatan elektron yang cukup tinggi yang menempati ketinggian 90 km hingga 130 km. Lapisan ini merupakan lapisan yang sangat bergantung pada aktivitas matahari. Pada lapisan E ini juga terdapat sublapisan yang bernama lapisan E Sporadis. Lapisan E sporadis merupakan lapisan terletak di ketinggian 95 hingga 130 km ini terkadang terjadi 50 % pada siang dan malam. Lapisan ini dimanfaatkan untuk frekuensi VHF dengan jarak jauh. 11 3. Lapisan F1 Lapisan ini merupakan lapisan ionosfer yang berada di atas lapisan E, yaitu pada ketinggian 160 km hingga 250 km. Konsentrasi electron dan ion pada lapisan ini sangat bergantung pada elevasi matahari. 4. Lapisan F2 Lapisan ini merupakan lapisan tertinggi dengan puncak ketinggian 250 km hingga 400 km, lapisan ini paling banyak menerima pancaran EUV sehingga kerapatan partikel bermuatannya juga paling tinggi. Konsentrasi elektron dan ion pada lapisan ini bergantung pada musim dan bintik matahari. Pada waktu malam hari, lapisan D dan E menghilang, sedangkan lapisan F1 dan F2 bergabung membentuk lapisan F. Gambar I.2 berikut menampilkan profil lapisan ionosfer. Gambar I. 2 Profil lapisan D, E, F1, dan F2 Ionosfer (Anderson dan Fuller-Rowell, 1999) 1.8.4.2. Anomali lapisan ionosfer. Pada lapisan inosfer terdapat molekul-molekul dan atom-atom yang terpecah dan membentuk sekumpulan paritikel bermuatan berupa elektron dan ion akibat dari adanya pengaruh radiasi Extreme Ultra Violet (EUV) matahari. Proses pembentukan ion ini dikenal dengan istilah ionisasi. Proses ionisasi 12 inilah yang menyebabkan lapisan ionosfer mengalami variasi. Variasi dapat berlangsung secara harian maupun musiman. Selain variasi, aktivitas matahari dapat menyebabkan adanya anomali di ionosfer. Anomali merupakan sebagai keadaan aneh yang terjadi di ionosfer. Saat aktivitas matahari mencapai puncak, maka kerapatan electron semua lapisan ionosfer meningkat. Sebaliknya saat aktivitas matahari menurun, kerapatan elektron semua lapisan ionosfer juga menurun (Rachman, 2013). Anomali pada lapisan ionosfer dapat terjadi dalam skala global maupun lokal. Anomali yang bersifat global merupakan anomali yang terjadi pada hampir seluruh lapisan ionosfer di semua belahan bumi, sedangkan anomali ionosfer lokal terjadi hanya pada lokasi dan daerah tertentu saja. Beberapa sebab anomali ionosfer global adalah badai geomagnet dan flare sedangkan salah satu penyebab anomali ionosfer yang bersifat lokal adalah adanya aktivitas seismik (Liperovsky, dkk., 2008). I.8.5 Total Electron Content (TEC) TEC adalah jumlah elektron dalam silinder yang luas penampangnya 1m2 dengan panjang silinder sejauh lintasan sinyal antara receiver dan satelit GNSS yang berada di lapisan ionosfer. Nilai TEC biasanya dinyatakan dalam TECU, dimana 1 TECU adalah sama dengan 1016 elektron/m2. Nilai TEC ionosfer biasanya berkisar antara 1 sampai 200 TECU (Abidin, 2000). Gambar I.3 memberikan ilustrasi hubungan antara slant total electron content (STEC), vertical total electron content (VTEC), dan ionospheric pierce point (IPP). STEC menyatakan jumlah elektron bebas pada silinder khayal pada garis pandang antara satelit dan receiver. VTEC menyatakan jumlah elektron pada silinder yang ditarik tegak lurus dari permukaan bumi. IPP merupakan titik potong lintasan sinyal GPS di ionosfer pada ketinggian tertentu (Ya'aqob dkk, 2008; Muslim, 2010). 13 Gambar I. 3 Ilustrasi dua dimensi STEC, VTEC dan IPP di lapisan ionosfer (Ya'aqob dkk, 2008) Subakti, dkk., (2008) menyatakan bahwa nilai TEC ditentukan dengan terlebih dahulu membentuk persamaan selisih waktu perlambatan antara L1 dan L2 pada GPS (∆Tion), yaitu sebagaimana tertulis pada Persamaan (3) : .............................................................. (3) TEC* dipindah ke ruas kiri menjadi Persamaan (4): ..................................................................... (4) Diketahui fL1 : 1575,42 MHz dan fL2 : 1227,6 MHz, kemudian STEC dicari dengan Persamaan (5) berikut : ....................................................................................... (5) dengan S(e) diketahui dari Persamaan (6) berikut : ............ (6) 14 Dalam hal ini R adalah jari-jari, h1 adalah ketinggian titik pertama, h2 adalah ketinggian titik kedua, dan e adalah sudut elevasi. Kemudian VTEC dicari dari persamaan (7) berikut : ...................................................... (7) Apabila tinggi ionosfer di Indonesia ialah 350 km (h = 350 km) dan jejari rerata bumi (R = 6378 km), dan E adalah sudut elevasi satelit GNSS, maka Persamaan (8) untuk menghitung nilai VTEC dapat ditulis sebagai berikut . .................................................................. (8) Muslim, dkk., (2010) menjelaskan bahwa penghitungan IPP dilakukan untuk mendapatkan dua komponen posisi titik potong, yaitu bujur dan lintang. Persamaan untuk menghitung bujur IPP ditunjukkan oleh Persamaan (9). 𝜆𝑝𝑝 = 𝑠𝑖𝑛−1 (𝑠𝑖𝑛 𝜆𝑢 . cos 𝜓𝑝𝑝 + 𝑐𝑜𝑠 𝜆𝑢 . sin 𝜓𝑝𝑝 . cos 𝐴) ............................... (9) dengan 𝜆𝑝𝑝 : bujur IPP 𝜆𝑢 : bujur stasiun pengamatan A : sudut azimuth satelit dari stasiun pengamatan 𝜓𝑝𝑝 : sudut di pusat bumi antara posisi stasiun pengamatan dengan proyeksi IPP ke permukaan bumi. Sudut ini dihitung dengan Persamaan (10). 𝜋 𝜓𝑝𝑝 = ̅ − 𝐸 − 𝑠𝑖𝑛−1 ((𝑅 . cos 𝐸) /(𝑅 + ℎ)) ...............................................(10) 2 dengan E : sudut elevasi satelit dari stasiun pengamat R : rerata jari-jari bumi 15 h : ketinggian lapisan ionosfer Selain dua komponen tersebut, terdapat satu komponen lain yaitu sudut elevasi IPP. Komponen posisi sudut elevasi titik IPP bernilai sama dengan sudut elevasi satelit GNSS (E). I.8.6 Badai Geomagnet Badai geomagnet terjadi akibat fenomena yang timbul di matahari terutama pada saat matahari aktif, yaitu berupa lontaran massa korona (Coronal Mass Ejection-CME) yang menyebabkan gangguan terhadap angin matahari dan berakibat pada peningkatan aktivitas medan magnet bumi yang akan memicu terjadinya badai geomagnet. Lontaran massa korona merupakan peristiwa terlontarnya plasma dalam jumlah besar dan membawa medan magnet dari matahari yang seringkali berasosiasi dengan flare. Materi ini menuju medium antar planet dan bila mengarah ke bumi akan mencapai bumi dalam waktu 1 s.d. 5 hari. CME ini dianggap sebagai salah satu penyebab terjadinya gangguan di ruang antar planet yang akan memicu terjadinya badai geomagnet (Webb, dkk., 2000). Sugiura dan Chapman (1960) mendefinisikan terminologi baru terkait indikator badai geomagnet, yaitu ’Disturbance storm time’ yang direpresentasikan sebagai indeks Dst, yang menggambarkan gangguan pada komponen H geomagnet saat terjadi badai. Subakti., dkk (2008) menjelaskan bahwa Disturbance Storm Time Index (Indeks Dst) adalah indeks geomagnet yang digunakan untuk menunjukkan level badai magnet global. Wetterer (2011) menjeaskan bahwa indeks Dst dihitung berdasarkan nilai rerata komponen horisontal medan magnet bumi diukur per jam pada empat magnetometer stasiun di dekat khatulistiwa dan direferensikan ke nol pada “internationally designated quiet days” Indeks Dst yang bernilai negatif menunjukkan adanya proses badai magnetik. Tanda negatif pada Indeks Dst disebabkan oleh arus badai yang melintasi bidang ekuatorial. Semakin kecil nilai indeks Dst yang ditunjukkan maka badai magnetik yang terjadi semakin besar. Indeks Dst dinyatakan dalam satuan nano Tesla (nT). Tingkat badai geomagnet dapat diklasifikasikan sebagai badai besar (Dst 16 < -100 nT), badai sedang (-100 nT < Dst < -50 nT) dan badai lemah (-50 nT < Dst < 30 nT). Data indeks Dst global dapat diunduh di http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/ Dst_realtime /index.html dan diketahui grafiknya. Gambar I.4 menampilkan grafik nilai indeks Dst selama 31 hari di bulan November 2104. Sumbu horizontal menunjukkan tanggal dalam bulan November Tahun 2014 sedangkan sumbu vertikal menyatakan nilai indeks badai geomagnet dengan satuan nano Tesla (nT). Gambar I. 4 Grafik nilai indeks Dst Bulan November 2014 (Nose, 2014) I.8.7 Seismo-Ionospheric-Coupling Seismo-Ionospheric Coupling menjelaskan bahwa aktivitas seismik yang terjadi di lapisan litosfer, akan membawa dampak berupa anomali di lapisan-lapisan ionosfer. Terdapat tiga lapisan ionosfer yang terkena dampak gempa bumi, yaitu lapisan D, lapisan E, dan lapisan F (Astra dan Pudja, 2009). Dampak yang terjadi adalah anomali pada kandungan elektron di ionosfer. Jumlah kandungan elektron akan mengalami kenaikan dan atau penurunan secara tidak wajar. Fenomena tidak wajar inilah yang disebut sebagai anomali ionosfer. Liu dkk., (2004) Menerangkan bahwa anomali ionosfer yang berhubungan dengan gempa bumi dapat terjadi beberapa hari sebelum maupun sesudah gempa bumi terjadi. Anomali ionosfer yang terjadi sebelum gempa bumi termasuk sebagai salah satu prekursor gempa bumi. Wahyu (2014) menjelaskan bahwa prekursor gempa bumi diartikan sebagai fenomena tidak lazim yang terjadi sebelum gempa bumi. Fenomena tersebut dapat berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan seismik, misalnya medan gravitasi, zat radioaktif, perubahan suhu air tanah, dan kondisi ionosfer. Beberapa fenomena ini dapat digunakan sebagai salah satu peringatan datangnya gempa bumi 17 yang kemudian dapat digunakan sebagai salah satu formula atau model untuk memprediksi datangnya gempabumi. Anomali ionosfer terjadi dengan interval waktu beberapa menit sampai beberapa jam. Interval waktu tersebut menunjukkan bahwa mekanisme Seismo-Ionospheric Coupling memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi (Meister, dkk., 2002). Liperovsky, dkk., (2008) menyatakan terdapat beberapa mekanisme seismoionospheric coupling, diantaranya adalah model gelombang akustik-grafitasi dan model medan listrik atmosfer. Model gelombang akustik-gravitasi merupakan hipotesis yang menyatakan bahwa sebelum terjadinya gempa bumi, terdapat peningkatan gelombang akustikgravitasi di sekitar episenter gempa bumi. Peningkatan gelombang ini diakibatkan oleh adanya panas yang disebabkan oleh adanya tekanan yang luar biasa pada lapisan batuan disekitar episenter. Gelombang ini menyebar melalui atmosfer dan mencapai lapisan ionosfer. Selanjutnya gelombang ini menyebabkan gangguan terhadap partikel-partikel bermuatan yang ada di ionosfer. Model medan listrik atmosfer merupakan model berdasarkan proses listrik yang terjadi dalam durasi yang singkat dan di jarak yang dekat dari episenter. Hipotesis ini mengemukakan bahwa sebelum gempa bumi terjadi, terdapat peningkatan jumlah bahan radioaktif di atmosfer. Unsur radioaktif meliputi radon, radium, torium, dan aktinium. Unsur radioaktif ini keluar di sekitar episenter dari bawah permukan bumi dan bersama aliran udara dapat mencapai lapisan ionosfer. Unsur-unsur ini mengandung partikel bermuatan yang dapat membentuk medan listrik. Medan listrik inilah yang mengakibatkan peningkatan ionisasi di ionosfer. Subakti., dkk (2008) menjelaskan bahwa besarnya dampak aktivitas seismik terhadap ionosfer berbanding terbalik dengan besarnya jarak terhadap episenter. Dengan kata lain, besarnya anomali yang terdeteksi oleh stasiun pengamatan juga sangat dipengaruhi oleh jaraknya terhadap episenter. Semakin jauh letak lokasi pengamatan terhadap episenter, maka dampak yang diterima semakin kecil. Akibatnya, anomali yang terdeteksi juga bernilai semakin kecil, demikian juga sebaliknya. Berdasarkan beberapa penelitian yang ada, terjadinya anomali ionosfer lokal memang belum mampu menjelaskan apakah gempa bumi pasti akan terjadi. Penelitian 18 yang dilakukan Tsolis dan Xenos (2009) dan Liu, dkk., (2013) mendapati adanya anomali ionosfer lokal yang belum dapat dikategorikan sebagai prekursor gempa bumi. Selain itu, meskipun anomali ionosfer yang memenuhi kriteria sebagai prekursor dapat dideteksi, hingga saat ini belum ada penelitian yang dapat memprediksi terjadinya gempa bumi secara akurat (Wahyu, 2014). Untuk itu, Tsolis dan Xenos (2009) menyarankan perlu adanya penelitian lebih lanjut prekursor maupun dampak gempa bumi. I.8.8 Gempa Bumi di Laut Maluku pada 15 November 2014 Menurut BMKG (2014), gempa bumi ini terjadi di Laut Maluku dengan episentrum 126,46 BT dan 1,95 LU dengan kekuatan 7,3 SR. Gempa ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 November 2014 pukul 09:31:44 WIB dengan kedalaman 48 km. Peta lokasi dan informasi gempa bumi ditunjukkan pada Gambar 1.5 berikut. Simbol bintang berwarna biru adalah letak episenter. Episenter berada di utara Laut Maluku yaitu di 158 km Timur Laut Bitung atau 160 km Barat Laut Ternate. Gambar I. 5 Lokasi dan informasi gempa bumi di Laut Maluku (BMKG, 2014) I.8.9 Analisis Korelasi Gangguan ionosfer oleh aktivitas seismik seperti gunung berapi, tsunami, dan gempa bumi sudah lama diteliti bahkan sebelum tahun 1965. Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan terhadap parameter total electron content (TEC) dan frekuensi kritis lapisan F2 (foF2) di sekitar wilayah episenter sebelum maupun sesudah aktivitas seismik terjadi (Jain dan Santosh, 2014). 19 Salah satu teknik yang digunakan dalam analisis prekursor dan efek gempa bumi adalah analisis korelasi dengan menggunakan parameter ionosfer. Metode yang dipakai dalam analisis seismo-ionospheric coupling ini adalah metode statistik, dimana parameter ionosfer dievaluasi selama beberapa hari sebelum dan beberapa hari sesudah kejadian gempa bumi. Tujuan utama dari metode tersebut adalah menunjukkan nilai deviasi yang signifikan pada parameter ionosfer yang diuji dari nilai median sebelum kejadian gempa (Tsolis dan Xenos, 2009). Metode ini merupakan metode yang stabil, namun masih terdapat gangguan geofisis dalam sinyal. Hal inilah yang mempersulit penentuan prekursor maupun efek gempa bumi. Gangguan fisis yang dimaksud misalnya badai geomagnet dan cuaca antariksa yang ikut mempengaruhi nilai fekuensi kritis lapisan F2 (foF2), TEC dan DTEC (Tsolis dan Xenos, 2009). Analisis korelasi ini terbagi atas dua jenis, yaitu korelasi silang dan autokorelasi. Sesuai dengan namanya, analisis korelasi merupakan analisis berdasarakan nilai koefisien korelasi. Winarsunu (2012) menjelaskan bahwa koefisien korelasi merupakan teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel. Dua variabel yang akan diteliti hubungannya tersebut adalah variabel terikat (variabel Y) dan variabel bebas (X). Apabila nilai koefisien korelasi antara X dan Y sudah dihitung, maka akan dapa ditentukan arah korelasinya. Arah korelasi dalam statistik ada tiga macam, yaitu : positif, negatif, dan nihil. Arah korelasi positif terjadi apabila kenaikan atau penurunan nilai pada varabel bebas (X) diikuti juga dengan kenaikan atau penurunan nilai pada variabel terikat (Y). Apabila kenaikan nilai variabel X diikuti dengan penurunan variabel Y, maka korelasi seperti ini memiliki arah korelasi negatif. Apabila variabel X dan Y tidak memiliki hubungan, maka korelasinya disebut nihil. Koefisien korelasi bergerak dari nilai -1,0 s.d. +1,0. Nilai korelasi -1,0 disebut korelasi negatif sempurna, nilai +1,0 disebut korelasi positif sempurna, sedangkan nilai 0 menunjukkan nihil korelasi. Nilai koefisien korelasi dapat dihitung dengan Persamaan (11) berikut. 𝑟𝑥𝑦 = dengan 𝑁.∑ 𝑋𝑌− ∑ 𝑋. ∑ 𝑌 √[(𝑁.∑ 𝑋 2 )−(∑ 𝑋)2 ] [(𝑁.∑ 𝑌 2 )−(∑ 𝑌)2 ] .................................... (11) 20 𝑟𝑥𝑦 : nilai koefisien korelasi antara variabel X dan Y N : banyaknya data ∑𝑋 : jumlah data pada variabel X ∑𝑌 : jumlah data pada variabel Y ∑ 𝑋𝑌 : jumlah data dari masing-masing variabel X yang dikali variabel Y ∑ 𝑋2 : jumlah data dari masing-masing variabel X yang dikuadratkan ∑ 𝑌2 : jumlah data dari masing-masing variabel Y yang dikuadratkan 1.8.9.1 Korelasi silang. Korelasi silang merupakan teknik untuk menguji korelasi antara dua atau lebih stasiun yang digunakan untuk mengamati prekursor maupun dampak gempa bumi. Variasi ionosfer di dekat episenter gempa bumi yang mengalami anomali dikorelasikan dengan variasi diurnal ionosfer di daerah lain yang jauh dari lokasi episenter gempa bumi. Pada saat tidak terjadi prekursor gempa bumi, koefisien korelasi daerah di dekat episenter gempa akan bernilai lebih rendah dibandingkan dengan nilai koefisien korelasi antara keduanya (Muslim, 2015). Pulinets dan Boyarchuk (2004) melakukan penelitian ini dengan menggunakan dua stasiun GPS untuk mendeteksi prekursor gempa bumi di San Siemon dari data total electron content (TEC). Satu stasiun GPS yang terletak di dekat episenter gempa bumi digunakan sebagai sensor anomali ionosfer dan stasiun GPS yang jauh dari episenter gempa bumi digunakan sebagai kontrol yang ionosfernya dianggap tidak terpengaruh gempa bumi. Melalui stasiun sensor dan kontrol, akan diketahui korelasi antara kedua stasiun tersebut. Jika terdapat anomali di stasiun sensor dan tidak terjadi di stasiun kontrol, maka nilai korelasinya akan rendah. Sebaliknya, jika tidak terjadi gangguan di salah satu stasiun GPS maka nilai korelasinya tetap tinggi. Jika terjadi gangguan di dua stasiun GPS tersebut yang disebabkan oleh badai geomagnet maka nilai korelasi variasi TEC antara dua lokasi tersebut juga tetap tinggi. 1.8.9.2 Autokorelasi. Autokorelasi merupakan analisis korelasi antara variasi diurnal ionosfer pada hari terjadinya prekursor gempa bumi dengan rata-rata variasi diurnal ionosfer di suatu tempat selama sattu bulan. Jika tidak terjadi prekursor gempa bumi 21 selama satu bulan pengamatan ionosfer, nilai koefisien korelasinya juga akan lebih rendah dibandingkan dengan nilai koefisien korelasi antara keduanya (Pulinets dan Boyarchuk, 2004). Muslim (2014) melakukan penelitian prekursor dan efek gempa bumi besar dengan kekuatan lebih dari 8,0 SR dengan menggunakan analisis autokorelasi. Penelitian tersebut dilakukan pada 17 gempa bumi besar yang terjadi di seluruh dunia sejak 16 November 2000 sampai dengan 11 Desember 2012. Data yang digunakan sebagai bahan penelitian adalah data TEC, indeks Dst, dan indeks Kp. Data TEC dipakai sebagai parameter kondisi ionosfer, sedangkan indeks Dst dan indeks Kp digunakan sebagai parameter badai geomagnet. Indeks Dst digunakan sebagai parameter badai geomagnet di daerah yang berlokasi di bagian bumi lintang rendah, sedangkan indeks Kp untuk lokasi lintang menengah dan tinggi. Analisis autokorelasi tersebut dilakukan dengan menghitung 31 koefisien korelasi autokorelasi antara variasi diurnal TEC pada hari tertentu dengan variasi diurnal nilai rata-rata tiap jam selama 31 hari. Dengan demikian, anomali sebelum dan sesudah gempa bumi dapat dideteksi. Simpangan koefisien korelasi harian kemudian dihitung terhadap nilai rerata koefisien korelasi (skk) selama 31 hari. Simpangan ini dibagi dengan standar deviasi koefisien korelasi (dskk) untuk digunakan sebagai indikator anomali ionosfer yang dijadikan sebagai dasar pengelompokan pengaruh gempa bumi pada ionosfer. Indikator anomali ionosfer yang disebabkan oleh gempa bumi maupun badai geomagnet ialah apabila nilai skk/dskk lebih kecil dari -1. Hasil tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan kriteria pada Gambar I.6. Gambar I. 6 Kriteria anomali ionosfer (Muslim, 2015) 22 Keterangan kriteria anomali ionosfer dijelaskan pada Tabel I.2. Tabel I.2 Keterangan kriteria anomali ionsofer (Muslim, 2015) No Kategori Keterangan 1 PGT Prekursor gempa bumi terdeteksi 2 PGT/EMT Prekursor gempa bumi/efek badai geomagnet terdeteksi 3 PGLT Prekursor gempa bumi lainnya 4 PGTT/EMTT Prekursor gempa bumi/efek badai geomagnet tidak terdeteksi 5 PGTT Prekursor gempa bumi tidak terdeteksi 6 EGT Efek gempa bumi terdeteksi 7 EMT Efek badai geomagnet terdeteksi 8 EGT/EMT Efek gempa bumi/badai geomagnet terdeteksi 9 EGTT Efek gempa bumi tidak terdeteksi 10 EMTT Efek badai geomagnet tidak terdeteksi Berdasarkan Gambar 1.6 dan Tabel I.2 dapat diketahui bahwa suatu anomali sebelum gempa dapat dinyatakan sebagai prekursor gempa yang terdeteksi (PGT) jika nilai skk dibagi dskk lebih kecil dari -1. Apabila daerah yang diteliti tersebut berada di lintang rendah, maka syarat lain yang harus dipenuhi adalah indeks Dst lebih besar dari -50 sebagai bukti tidak adanya badai geomagnet pada saat itu. Namun apabila episenter berada di lintang tinggi, maka nilai indeks Kp harus lebih kecil dari 4. Demikian juga untuk kategori lainnya, keempat syarat yang tercantum harus terpenuhi agar dapat diklasifikasikan pada masing-masing kategori. 1.9. Hipotesis Beberapa hari sebelum gempa bumi di laut Maluku pada 15 November 2014, akan terjadi anomali di lapisan ionosfer. Anomali yang terjadi merupakan prekursor gempa bumi tersebut.



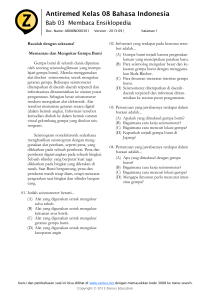

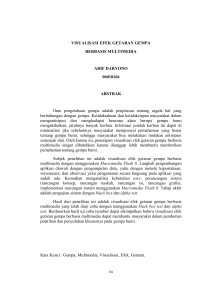

![Gempa Bumi baru [Compatibility Mode]](http://s1.studylibid.com/store/data/000103501_1-93426cf2450b61129358ad71a5f94423-300x300.png)