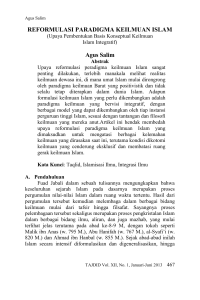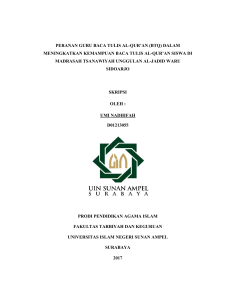Ilmu Hukum Profetik Gagasan Awal Landasan Kefilsafatan
advertisement

Penyunting M. Syamsudin Kontributor: Prof. Dr. M. Koesnoe, S.H. Prof. Heddy Shri Ahimsa Putra, M.A., M.Phill., Ph.D. Prof. Dr. Amin Abdullah Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum. FH UII Press ILMU HUKUM PROFETIK Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodern Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H. (Penyunting) Cetakan Pertama, Desember 2013 xiv + 312 hlm Sampul : Rano Lay out: M. Hasbi Ashshidiki Penerbit Pusat Studi Hukum (PSH) FH UII kerjasama dengan FH UII Press Jl. Tamansiswa 158 Yogyakarta PO BOX. 1133 Phone: 379178 [email protected] ISBN: 978-602 -1123-01-0 v KATA SAMBUTAN Bismillahirrahmanirrahiem, Assalamu’alaikum Wr.Wb. Pertama- tama saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII yang telah berhasil menerbitkan buku berjudul: ILMU HUKUM PROFETIK Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodern. Saya kira buku ini adalah buku yang pertama kali hadir untuk mewacanakan tentang Ilmu Hukum Profetik di tengah-tengah para penstudi hukum. Semangat dari kehadiran buku ini nampaknya tidak terlepas dari upaya pencarian dan penemuan kebenaran di tengahtengah krisis epistemologi Ilmu Hukum Modern yang terbukti telah banyak membawa problem terhadap peradaban manusia. Epistemologi Ilmu Hukum modern telah menjauhkan manusia dari nilai-nilai hukum yang berbasis pada nilai-nilai ketuhanan (transendensi), sehingga melahirkan cara berilmu hukum dengan karakter materialistik, pragmatik, hedonis dan atheistik yang telah menyebabkan dehumnaisasi, karena manusia berjalan sendiri tanpa petunjuk (huda) dari Yang Maha Kuasa. (wahyu). Setelah saya membaca isi naskah buku tersebut, ternyata isinya tidak jauh berbeda dengan semangat dan gagasan yang pernah vi Kata Sambutan diwacanakan di lingkungan FH UII pada tahun 90-an yang kemudian terumuskan dalam Pola Ilmiah Pokok (PIP) FH UII. Pola Ilmiah Pokok tersebut berfungsi sebagai norma dasar akademis yang memberi arah seluruh aktifitas di FH UII yang dinyatakan di dalam keseluruhan kurikulum, silabus dan kegiatan akademik penunjang. Mengacu pada PIP tersebut pendidikan di FH UII diberi tema PENEGAKAN HUKUM YANG BERWAWASAN QURANI. Oleh karena itu FH UII sangat berkepentingan dan menyambut baik terbitnya buku tersebut. Saya menganjurkan kepada para dosen dan juga mahasiswa hukum untuk membaca buku tersebut, kemudian melakukan diskusi terhadap gagasan-gagasan yang dimunculkan pada buku tersebut. Terakhir saya ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada Sdr.M.Syamsudin dkk di Pusat Studi Hukum (PSH) yang telah merancang kegiatan serial diskusi yang membicarakan tentang Ilmu Hukum Profetik ini, yang kemudian hasilnya diwadahi dalam bentuk buku yang terbit kali ini. Saya berharap pengkajian Hukum Profetik tidak berhenti sampai sebatas diterbitkan buku ini, tapi terus dikaji dan dikaji sampai jelas sosok dan struktur keilmuanya. Saya kira buku ini baru membahas dari aspek filsafat keilmuan hukumnya belum sampai pada strukturnya, seperti apa sebenarnya Ilmu Hukum Profetik itu. Ini yang perlu dikembangkan lebih lanjut oleh PSH. Selamat membaca buku ini dan terimakasih. Wassalamu’alaikum Wr.Wb. Yogykarta, Desember 2013 Dekan FH UII, Ttd Dr. H.Rusli Muhammad, S.H.,M.H. vii KATA PENGANTAR Bismillahirrahmaanirrahiem, Segala puji dan pujian hanya milik Allah, Tuhan seru sekalian alam, hanya kepada Mu kami menyembah, mohon petunjuk, pertolongan dan tambahan ilmu pengetahuan. Berkat Rahmat dan hidayahMu alhamdulillah naskah buku yang sederhana ini dapat terselesaikan dan kemudian tersajikan di hadapan para pembaca yang budiman yang sangat mencintai ilmu pengetahuan. Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSH FH UII) Yogyakarta pada periode kepengurusan 2010-2014 telah menyelenggarakan Program Paket Serial Diskusi dengan Topik “Menggagas Ilmu Hukum Berparadigma Profetik sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum di FH UII”. Tujuan dari diskusi tersebut dirancang untuk menggali, menemukan dan kemudian membangun Ilmu Hukum berbasis pada Paradigma Profetik serta untuk mengembangkan kemungkinan pendidikan hukum yang berbasis pada Ilmu Hukum Profetik sebagai Local Genius di FH UII Yogyakarta. Diskusi tersebut berlangsung selama 4 (empat) seri dengan menghadirkan para nara sumber yang kompeten, yaitu: Seri I, Prof. Dr. Erlin Indarti, S.H.,M.A. (dosen FH Undip Semarang); dan Dr. Mudzakir, S.H.,M.H. (dosen FH UII) dengan topik bahasan ‘Meninjau Perkembangan viii Kata Pengantar Paradigma Keilmuan dan Implikasinya pada Keilmuan Hukum di Era Postmodern’. Seri II, Prof. Heddy Shri Ahimsa Putra, M.A., M.Phill.,Ph.D. (Dosen Fakultas Ilmu Budaya UGM) dan Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H. (dosen FH UII) dengan topik bahasan ‘Paradigma Profetik dan Kemungkinan Aplikasi dan Pengembangannya bagi Keilmuan Hukum’. Seri III, Prof. Dr. Amin Abdullah (dosen UIN Sunan Kalijaga) dan Prof. Jawahir Thonthowi, S.H.,Ph.D. (dosen FH UII), dengan topik bahasan ‘Perkembangan Filsafat Hukum Islam dan Implikasinya pada Keilmuan Hukum’. Seri IV, Prof. Heddy Shri Ahimsa Putra, M,A.,M.Phill.,Ph.D. (dosen Fakultas Ilmu Budaya UGM) dan Dr. Busjro Muqoddas, SH.,M.Hum. (dosen FH UII) dengan topik pembahasan ‘Menggagas Ilmu Hukum Berbasis Paradigma Profetik Ditinjau dari Filsafat Ilmu dan Ilmu Hukum’. Dari hasil serial diskusi tersebut terkumpul beberapa makalah dari para nara sumber dan makalah-makalah tersebut menjadi materi pokok buku ini yang diberi judul ILMU HUKUM PROFETIK, Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodern. Namun sayangnya tidak semua materi dari nara sumber dapat tertampung dalam naskah buku ini, karena ada sebagian makalah dalam bentuk power point, sehingga tidak dapat diterbitkan. Dari materi pokok tersebut kemudian diperkaya dan dikembangkan dengan makalah pendukung lain yang ditulis oleh para dosen FH UII dengan pembagian topik-topik tertentu. Sebagaimana judulnya, buku ini dihadirkan dan diwacanakan kepada sidang pembaca lebih-lebih para pecinta ilmu (ilmuwan) untuk mengajak dan sekaligus menantang untuk mencari dan menemukan gagasan baru tentang perlunya pengembangan Ilmu Hukum yang berparadigma profetik. Bagi Ilmu Hukum sendiri, munculnya Paradigma Profetik yang digagas oleh Kuntowijoyo dan dilanjutkan oleh Heddy Shri Ahimsa-Putra, terasa mendapatkan ideologi baru yang patut diwadahi dan kemudian dikembangkan sebagai alternatif kajian ilmu hukum di tengah-tengah situasi krisis epistemogi keilmuan hukum modern barat. Pada tahapan awal hal penting dan mendasar yang ditawarkan dalam buku ini adalah mencari ix landasan kefilsafatan dari ilmu hukum profetik. Buku ini pada intinya telah mencoba menguraikan konsep paradigma profetik yang kemudian dijabarkan menjadi dasar filosofi keilmuan hukum profetik baik dari dimensi ontologis, epistemologis maupun aksiologisnya. Untuk selanjutnya sosok dan struktur dari Ilmu Hukum Profetik itu sendiri masih membutuhkan kerja keras untuk penjabaran lebih lanjut. Dalam proses penulisan buku ini, banyak pihak yang telah menyumbangkan kontribusinya baik berupa gagasan / pikiran, tenaga dan finansial yang tak terhitung nilainya pada penulisan buku ini, sehingga buku ini dapat hadir dan tersaji di hadapan para pembaca. Oleh karena itu sudah sepatutnya kami mengucapkan banyak terimakasih kepada: 1. Dekan FH UII, Dr. Rusli Muhammad, S.H.,M.H, dan juga Wakil Dekan Dr. Saifudin, S.H,M.H., yang telah banyak mendukung dari aspek kebijakan program dan anggaran finansial kepada PSH pada acara diskusi dan juga proses penerbitan buku ini; 2. Para nara sumber dan kontributor yang telah mensedekahkan ilmunya atau makalahnya pada serial diskusi dan juga naskah buku ini, semoga ilmunya bermanfaat dan menjadi amal jariyah yang tidak terputus; 3. Para dosen dan karyawan FH UII yang telah banyak berkontribusi pada kegiatan diskusi dan penulisan buku ini; 4. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu dalam kesempatan ini. Kami berdo’a, mudah-mudahan amal baik semua pihak mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Mudah-mudahan pula karya yang sederhana ini dapat bermanfaat untuk pengembangan keilmuan hukum baik secara teoretis maupun praktis. Amien. Yogyakarta, Desember 2013 Kepala Pusat Studi Hukum (PSH) FH UII Periode 2010-2014 Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H. x DAFTAR ISI Kata Sambutan ~ v Kata Pengantar ~ vii Daftar Isi ~ x BAB 1 : PENDAHULUAN Oleh M. Syamsudin A. Memahami Persoalan Keilmuan dan Ilmu Hukum Dewasa ini ~ 1 B. Urgensi Kehadiran Ilmu Hukum Profetik ~ 7 C. Apa dan Mengapa Digunakan Istilah Profetik? ~ 14 D. Sistematika dan Deskripsi Muatan Isi Buku ~ 19 BAB 2 : PARADIGMA PROFETIK (Sebuah Konsepsi) Oleh Heddy Shri Ahimsa-Putra A. Pengantar ~ 25 B. Paradigma: Apa itu? ~ 28 1. Paradigma: Sebuah Definisi ~ 29 2. Unsur-unsur (komponen-komponen) Paradigma ~ 32 3. Skema Paradigma ~ 44 C. Paradigma Profetik dan Islam ~ 47 1. Basis Epistemologis ~ 47 Daftar Isi xi 2. 3. 4. 5. 6. Asumsi Dasar tentang Basis Pengetahuan ~ 51 Asumsi Dasar tentang Obyek Material ~ 56 Asumsi Dasar tentang Gejala yang Diteliti ~ 57 Asumsi Dasar tentang Ilmu Pengetahuan ~ 58 Asumsi Dasar tentang Ilmu Sosial dan/atau Alam Profetik ~ 59 7. Asumsi Dasar tentang Disiplin Profetik ~ 60 D. Etos Paradigma Profetik ~ 60 1. Basis Semua Etos: Penghayatan ~ 61 2. Etos: Pengabdian ~ 62 3. Etos Kerja Keilmuan ~ 64 4. Etos Kerja Kemanusiaan ~ 65 E. Model Paradigma Profetik ~ 67 1. Model (Struktur) Rukun Iman dan Transformasinya ~ 67 2. Model (Struktur) Rukun Islam dan Transformasinya ~ 70 F. Implikasi Epistemologi Profetik ~ 72 1. Implikasi Permasalahan ~ 73 2. Implikasi Konseptual ~ 73 3. Implikasi Metodologis Penelitian ~ 74 4. Implikasi Metodologis Analisis ~ 74 5. Implikasi Teoretis ~ 74 6. Implikasi Representasional (Etnografis) ~ 75 G. Implikasi Paradigma Profetik ~ 75 1. Transformasi Individual ~ 75 2. Transformasi Sosial (Kolektif) ~ 76 H. Penutup ~ 77 BAB 3 : LANDASAN ONTOLOGI PROFETIK Oleh M. Syamsudin ILMU HUKUM A. Pengatar ~ 79 B. Pengaruh Paradigma Positivisme pada Ontologi Ilmu Hukum ~ 85 C. Pengaruh Paradigma Post-Positivisme pada Ontologi Ilmu Hukum ~ 89 xii D. Posisi Ilmu Hukum di Tengah Perkembangan berbagai Paradigma ~ 91 E. Ontologi Hukum sebagai Wilayah Terbuka ~ 95 F. Dimensi Ontologi dalam Ilmu Hukum Profetik ~ 100 BAB 4 : LANDASAN EPISTEMOLOGI ILMU HUKUM PROFETIK A. Pengantar ~ 109 B. Meninjau Pemikiran Ilmu, Ilmiah Modern dan Dasar Filsafatnya Dewasa Ini, Suatu Tinjauan dalam Rangka Persepektif Wawasan Ajaran Ke-Islaman ~ 110 Oleh M.Koesnoe 1. Pendahuluan (1) ~ 110 2. Tatanan Pemikiran Menuju ke Pemikiran Ilmu dan Ilmiah ~ 111 3. Hubungan Pemikiran Ilmu dan Ilmiah dengan Filsafat ~ 115 4. Dasar Filsafati Pemikiran Ilmu dan Ilmiah Modern ~ 116 5. Ajaran Islam tentang Pengetahuan dan Pemikiran Keilmiahan ~ 125 6. Pendahuluan (2) ~ 127 7. Andalan Utama tentang Dasar Kemampuan Mengetahui Manusia ~ 133 8. Dinamika Kegiatan Keilmuan dan Keilmiahan Kaum Muslimin ~ 135 9. Mencari Keseimbangan ~ 138 10.Ilmu dan Keilmiahan dalam Wawasan Ke-Islaman ~ 145 11.Penutup ~ 151 C. Prinsip-Prinsip Epistemologi tentang Pengembangan Ilmu pengetahuan di dalam al-Qur’an ~ 154 Oleh M. Syamsudin D. Paradigma Profetik dalam Hukum Islam Melalui Pendekatan Systems ~ 161 Oleh Amin Abdullah Daftar Isi xiii 1. Pendahuluan ~ 161 2. Respon Intelektual Muslim Kontemporer terhadap Perubahan Sosial ~ 162 3. Progressif-ijtihadi dalam Tafsir al-Qur’an: Abdullah Saeed ~ 168 4. Pendekatan Systems dalam Hukum Islam: Jasser Auda ~ 172 5. Keutamaan Etika/the Primacy of Ethics ~ 204 6. Penutup ~ 207 E. Basis Epistemologi Ilmu Hukum Profetik ~ 209 Oleh M. Syamsudin 1. Asumsi Dasar tentang Basis Pengetahuan ~ 215 2. Asumsi Dasar tentang Objek Material ~ 217 3. Asumsi Dasar tentang Disiplin ~ 219 BAB 5 : LANDASAN PROFETIK AKSIOLOGI ILMU HUKUM A. Pengantar ~ 221 Oleh M. Syamsudin B. Paradigma Profetik dalam Pengembangan Pendidikan Hukum ~ 224 Oleh Jawahir Thontowi 1. 2. 3. 4. 5. Pendahuluan ~ 224 Makna dan Fungsi Paradigma ~ 226 Paradigma dan Filsafat Ilmu Hukum ~ 232 Pemikiran Hukum Paradigmatik Pancasila ~ 236 Paradigma Profetik dalam Pengembangan Ilmu Hukum ~ 238 6. Simpulan ~ 245 C. Hakim Butuh Profetik Intelelligence dalam Memutuskan Perkara di Pengadilan ~ 247 Oleh M. Syamsudin 1. Pendahuluan ~ 247 2. Faktor-faktor Non-Legal yang Ikut Mempengaruhi Hakim dalam Memutuskan Perkara ~ 250 xiv 3. Arti Penting Profetik Intelligence bagi Hakim dalam Memutuskan Perkara ~ 258 4. Simpulan ~ 262 D. Hakim dan Penegakan Keadilan Profetik dalam Peradilan ~ 263 Oleh Bambang Sutiyoso 1. Pendahuluan ~ 263 2. Tugas dan Kewajiban Hakim ~ 266 3. Eksistensi Peradilan dalam Menegakkan Keadilan ~ 269 4. Konsep Keadilan Putusan dalam Peradilan ~ 276 5. Keadilan Profetik dan Implementasinya dalam Peradilan ~ 283 6. Penutup ~ 285 BAB 6 : PENUTUP Oleh M. Syamsudin A. Menangkap Peluang di Era Posmodern ~ 287 B. Ilmu Hukum Profetik sebagai Tawaran Alternatif ~ 291 DAFTAR PUSTAKA ~ 301 BIODATA PENULIS ~ 309 BAB 1 PENDAHULUAN Oleh M. Syamsudin A. Memahami Persoalan Keilmuan dan Ilmu Hukum Dewasa ini Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan menunjukkan antara lain bahwa hubungan antara ilmu pengetahuan dan agama (sistem kepercayaan) tidak selalu harmonis dan bahkan terkadang dipertentangkan. Antagonisme antara keduanya sebagaimana diwakili oleh masing-masing pendukungnya sempat mempengaruhi kehidupan orang banyak dalam jangka waktu yang cukup lama, bahkan terkadang sekarang ini masih sering terdengar. Pertentangan itu mula-mula tampak terhadap semua cabang ilmu pengetahuan, baik ilmu-ilmu alam (natural sciences) maupun ilmu-ilmu sosial (social sciences). Tetapi saat ini rasanya sudah jarang terdengar bahwa agama menentang suatu perkembangan ilmu pengetahuan alam atau sebaliknya. Walaupun begitu, pertentangan antara agama terhadap perkembangan ilmu-ilmu sosial masih dirasakan sebagai sesuatu yang terus berlangsung. Pertentangan itu bila dikaji lebih dalam tidaklah mengherankan, sebab keduanya mempunyai etikanya masing-masing yaitu bahwa agama menuntut adanya sikap menerima dengan teguh, tanpa ragu dan dengan kepastian tentang hasil kesudahan. Sementara ilmu pengetahuan justru sebaliknya yaitu dilandaskan kepada skeptisisme Pendahuluan 2 dan sikap tidak berkepentingan (disinterestedness) akan hasil kesudahan suatu kegiatan ilmiah, selain nilai ilmiah itu sendiri. Lebih tidak mengherankan lagi adanya pertentangan itu, sebab antara ilmu-ilmu sosial saja yang berlandaskan etika yang sama sering terjadi benturan. Pada zaman modern ini pertentangan-pertentangan ideologi yang banyak mempengaruhi kehidupan manusia, bukan antara yang agama dan yang duniawi (sekuler) tetapi justru antara yang samasama sekuler yaitu kapitalisme dan komunisme.1 Sebuah contoh yang patut dikemukakan di sini apabila dibuka lembaran sejarah masa lalu tentang pertentangan antara ilmu pengetahuan dan agama adalah peristiwa tragis dan berdarah tentang pembakaran Perpustakaan Iskandaria yang dilanjutkan dengan pembunuhan para ilmuwan yang disponsori oleh Gereja Kristen pimpinan Uskup Agung Iskandaria Cyril yang sehabis melaksanakan tugas yang dianggap suci itu kemudian diberi kehormatan oleh gereja sebagai Orang Suci atau Santo. Perpustakaan Iskandaria pada waktu itu kaya akan buku-buku keilmuan hasil karya para ilmuwan pada waktu itu. Misalnya Earastothenes, seorang ahli ilmu bumi, astronom, ahli sejarah, filsafat, matematika, penyair, dan kritikus teater; Hiparchus, yang mencoba membuat peta konstalasi bintang-bintang dan mengukur tingkat cahaya bintang-bintang itu; Euclidus, penemu sebenarnya ilmu ukur atau geometri; Dionysius, yang meneliti organ-organ suara manusia dan meletakkan teori tentang bahasa; Herophus, ahli ilmu faal atau fisiologi yang menegaskan bahwa organ berpikir manusia bukanlah jantung sebagaimana diyakini saat itu, melainkan otak; Heron, penemu rangkaian roda gigi dan penemu mesin uap kuno, pengarang buku aotomata, sebuah buku pertama tentang robot; Apolonius, yang meletakkan teori tentang bentuk melengkung seperti ellips, parabola dan hiperbola; Archimides, genius mekanik terbesar sebelum Leonardo da Vinci; Holomy, seorang yang walaupun teorinya tentang alam raya Nurcholis Madjid. 1993. Islam, Kemodernan dan Ke-Indonesiaan, Bandung: Mizan. Hlm. 264-265. 1 Bab 1 3 ternyata salah (geosentris) namun semangat keilmuannya banyak memberi ilham; dan Hypatia, seorang wanita ahli matematika dan astronomi yang mati terbakar bersama perpustakaan dan segenap isinya berupa buku-buku ilmiah di atas papirus bertulis tangan sebanyak sekitar setengah juta buah, tujuh abad setelah perpustakaan itu didirikan.2 Peristiwa tragis itupun masih terus berlanjut, sehingga pada tahun 1833 Galileo harus menjalani inkuisisi Gereja, dipaksa untuk mencabut pernyataannya bahwa bumi berputar mengelilingi matahari,3 dan masih banyak lagi para ilmuwan yang merelakan nyawanya berhadapan dengan otoritas pengadilan gereja. Perkembangan terakhir yang masih menyedihkan pada zaman modern ini adalah bahwa kaum Kristen modern terutama kalangan fondamentalis banyak yang menolak Teori Evolusi Darwin dan hanya berpegang pada bunyi harfiah ajaran penciptaan atau kreasi dalam Genesis. Di Amerika kaum evolusionis dari kalangan ilmuwan berhadapan dengan kaum kreasionis dari kalangan Kristen fondamentalis.4 Konflik yang tak terdamaikan antara agama dan ilmu pengetahuan yang terjadi di dunia barat itu berakibat adanya pemisahan yang sangat tajam antara agama dan ilmu pengetahuan dan hal lain yang bersifat sekuler yaitu kehidupan agama dengan negara. Inilah sebenarnya penyebab terjadinya krisis epistemologis keilmuan dan problem moral di dunia barat modern saat ini. Konflik itu ternyata telah dimenangkan oleh para ilmuwan dan segera setelah itu muncul babak baru di dunia barat yaitu masa reneisance yang telah melahirkan abad modern Eropa Barat dengan perkembangan yang sangat pesat ilmu pengetahuan dan teknologi. Nurcholis Madjid. 2005. Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan . Jakarta: Penerbit Paramadina. Hlm. xxxi. 3 Jujun S. Suriasumantri. 1994. Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hlm. 233. 4 Nurcholis Madjid. 2005. Op.Cit. Hlm. xxxii. 2 Pendahuluan 4 Namun demikian apabila kita mau menengok sejarah perkembangan ilmu pengetahuan modern barat itu tidak dapat lepas dari masa-masa sebelumnya yaitu masa pengembangan ilmu pengetahuan klasik Islam pada abad ke-7 sampai dengan ke-14 M. Peradaban Islam telah diakui oleh para sarjana modern bahwa kemajuan barat itu sendiri adalah berkat sumbangan bahan-bahan dari peradaban Islam Klasik. Islam mempunyai jasa besar terhadap peradaban manusia yaitu meng”internasionalkan” ilmu pengetahuan yang sebelumnya suatu cabang ilmu pengetahuan hanya merupakan kekayaan nasional bangsa tertentu seperti Yunani, Persi, India dan Cina. Gustav Le Bon merekam peristiwa masa-masa tersebut dalam bukunya The World of Islamic Civilization mengemukakan bahwa pada saat Arab Islam dalam puncak kecemerlangan peradaban kreatifnya, pengaruhnya terhadap bangsa-bangsa lain tidak ada taranya dalam sejarah. Pengaruh ini tidak terbatas pada kawasan Asia-Afrika, tetapi juga jantung Eropa ditembusnya. Pada abad ke-9 dan ke-10, yaitu pada saat pusat-pusat Islam di Spanyol sedang berada di puncak kecemerlangannya, pusat-pusat intelektual di barat hanyalah berupa benteng-benteng perkasa, dihuni oleh para bangsawan semi-barbarik yang dirinya merasa bangga atas ketidakmampuannya membaca. Perkenalan dengan peradaban Islamlah sebenarnya yang membawa Eropa menjadi dunia beradab.5 Apa yang dilakukan oleh orang Islam ketika meluaskan daerah pengaruhnya dalam masa-masa tersebut? Le Bon menjawab: “Jika menaklukkan sebuah kota, yang pertama mereka (muslim) lakukan adalah mendirikan masjid dan sekolah.6 Dua bangunan ini menunjukkan betapa generasi awal Islam telah mampu merumuskan dan mempraktikkan dengan nyata perlunya perpaduan secara seimbang Gustav Le Bon. 1974. The World of Islamic Civilization, terj. oleh David Macrae. Todor Publishing Company. Hlm. 138-139. Baca pula Syafi’i Maarif. 1993. Peta Bumi Intelektual Muslim di Indonesia. Bandung: Mizan. Hlm. 34. 6 Ibid. Hlm 25. 5 Bab 1 5 antara dimensi spiritual dan dimensi dunia (sekuler). Hal ini merupakan terjemahan nyata dari firman Allah tentang manusia Ulul Albab7 yaitu mereka yang memadukan dengan seimbang antara dzikir dan fikir, antara hati dan otak. Masjid adalah tempat dan sekaligus wujud kesadaran pentingnya kontak yang konkrit dengan Allah SWT, dan sekolah adalah tempat dan sekaligus wujud kesadaran bahwa otak manusia perlu dilatih berfikir guna memahami konsep-konsep keseluruhan alam raya ini. Pada periode kreatif dan dinamis di Eropa Barat ini berlangsung sekitar lima abad, dan di antaranya telah berhasil mengembangkan metode induktif dalam mendekati gejala alam. Sebelumnya sarjanasarjana muslimlah yang merintis metode eksperimen dan observasi yang kemudian dikembangkan oleh para penerusnya di dunia barat. Le Bon membuat lagi perbandingan yang menarik antara dunia Islam dan Eropa abad pertengahan dengan mengatakan: “eksperimen dan observasi adalah metode Arab. Kajian buku dan pengulangan opini tuannya adalah metode Eropa abad pertengahan. Perbedaan ini begitu fundamental untuk memahami jasa-jasa ilmiah Arab-Islam. Sarjana Muslimlah dalam sejarah yang pertama kali menyadari pentingnya metode ini.”8 Di samping metode induktif, yang juga mendapat perhatian dan berhasil sangat mengagumkan adalah pengembaraannya ke wilayah kajian spekulatif. Karya-karya Filsafat dan Sufisme Islam yang monumental adalah buah dari pengembarannya itu. Deretan nama semisal Al Kindi, Al Farabi, Ibnu Sina, Al Ghozali, Ibnu Arabi, Ibnu Rusyd, Ibnu Khaldun, adalah diantara nama-nama yang selalu disebut dalam sejarah. Begitu juga Ibnu Taimiyah yang dipandang sebagai peletak dasar pertama dari bangunan pemikiran Islam modern adalah hasil abad kreatif itu.9 Namun apabila kita melihat dunia Islam saat ini amatlah menyedihkan terutama dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan 7 8 9 Alquran. S. Ali Imran, ayat 190-191. Safi’i Ma’arif. 1993. Op.Cit. Hlm. 25. Ibid. Hlm. 25. Pendahuluan 6 teknologi. Sebagaimana disinyalir oleh C.A Qodir bahwa sekarang ini di negeri-negeri muslim praktis tidak ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk keamanan dan kebutuhan pembangunan mereka harus menggantungkan diri kepada teknologi yang mereka pinjam dan beli dengan harga yang mencekik leher dari barat dan kadang-kadang dari Rusia dan Jepang.10 Dalam konteks Indonesia sendiri sebagai negeri yang dapat dibilang muslim, pada dekade tahun tujuh puluhan dan delapan puluhan muncul suatu kesadaran baru di kalangan akademisi dan ilmuwan muda muslim mengenai adanya krisis di bidang keilmuan modern, baik terkait dengan ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial. Krisis itu konon terkait dengan asumsi dasar dari bangunan ilmu modern itu sendiri yang dianggap bebas nilai dan bebas kepentingan lainnya. Implikasi dari ilmu yang dikonstruksikan seperti itu, membawa dampak pada aspek epistemologi dan aksiologi ilmu. Artinya kebaikan atau keburukan ilmu tidak tergantung kepada produk dari ilmu yang berupa teknologi, teori-teori, doktrin dan kebijakan, akan tetapi lebih tergantung kepada penggunaan dari ilmu itu oleh manusia, apakah dimanfaatkan untuk kebaikan atau keburukan. Fenomena krisis keilmuan tersebut, ditanggapi dengan gagasan perlunya dimensi etika dalam pengembangan ilmu. Dalam kazanah pemikiran sosialisme muncul teori ekonomi dependensia, ekonomi kerakyatan, dan ilmu sosial kritis. Dalam kazanah pemikiran Islam berkembang ide islamisasi ilmu pengetahuan, termasuk islamisasi ilmu-ilmu sosial.11 Dalam konteks global, realitas perkembangan ilmu modern pada waktu sekarang ini juga ditandai oleh adanya krisis ekonomi dan keuangan, khususnya terjadi di Amerika Serikat dan Uni Eropa (sebelumnya juga Asia) yang disebabkan oleh sistem ekonomi pasar C.A. Qodir. 1991. Filsafat dan Ilmu Pengetahuan dalam Islam. Jakarta: Yayasan Obor. Hlm. 191. 11 Salman Luthan. 2011. “Gagasan Ilmu Hukum Profetik”. Makalah disampaikan dalam Diskusi Pengembangan Ilmu Profetik 2011,diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum - UII, di Yogyakarta, 18 Nopember 2011. 10 Bab 1 7 yang tidak mampu mendorong mekanisme pasar yang sehat dan berkeadilan. Penolakan dan gugatan terhadap sistem ekonomi pasar semakin mengemuka belakangan ini. Seiring dengan gugatan terhadap sistem ekonomi pasar, sistem hukum liberal yang menjadi basis positivisme hukum sebagai penopang ekonomi pasar juga ikut digugat. Sistem hukum liberal dengan doktrin kompetisi bebas dan perlindungan yang sama bagi semua kekuatan ekonomi melegitimasi hegemoni negara-negara besar terhadap negara-negara kecil, negara-negara kaya terhadap negara-negara miskin.12 Di Indonesia sendiri, problematika hukum domestik ditandai dengan fenomena-fenomena antara lain: supremasi hukum dan sistem hukum yang lemah, kualitas undang-undang yang rendah, konflik antar norma undang-undang, misalnya konsep kerugian negara, putusan hakim yang saling bertentangan, konflik hukum formal dan hukum substansial, konflik hukum negara dan dan hukum masyarakat, khususnya kasus tanah-tanah adat.13 Sementara itu penegakan hukum di Indonesia juga menunjukkan problematika antara lain: rendahnya kredibiltas lembaga peradilan, rendahnya kualitas putusan hakim, adanya putusan hakim saling bertentangan, kualitas sumber daya manusia (SDM) rendah, adanya konflik penafsiran tekstual dengan penafsiran kontekstual, konflik keadilan prosedural dan keadilan substansial, konflik keadilan retributif dan keadilan restoratif, konflik kepastian hukum dan keadilan, dan sebagainya.14 B. Urgensi Kehadiran Ilmu Hukum Profetik Ilmu Hukum adalah salah satu ilmu yang sudah dikenal sebagai cabang ilmu yang nilai ilmiahnya sudah tidak diragukan lagi. Ilmu Hukum entah sebagai Ilmu Hukum Positip maupun sebagai Teori 12 13 14 Ibid. Ibid. Ibid. 8 Pendahuluan Hukum dianggap sudah benar-benar ilmiah. Bahkan menurut Harold J. Berman, berdasarkan penulusuran historis yang luas dan mendalam, Ilmu Hukum merupakan ilmu modern pertama yang lahir di dunia barat. Ilmu Hukum sebagaimana yang dikenal sekarang ini timbul pada penghujung abad ke-12 bersamaan dengan lahirnya universitas.15 Ilmu Hukum yang diajarkan di berbagai Fakultas Hukum di Indonesia sekarang ini sebenarnya adalah berasal dari Ilmu Hukum Barat yang ada di Daratan Eropa (continental). Secara formal, bangsa Indonesia mengenal dan memperoleh Ilmu Hukum untuk pertama kalinya dari bangsa Belanda dengan didirikannya Rechtsschool pada tahun 1909, yang kemudian dikembangkan menjadi Rechtshogeschool di Jakarta pada tahun 1924. Ilmu Hukum yang diajarkan dengan sendirinya adalah Ilmu Hukum Nasional Belanda yang tentunya sudah disesuaikan dengan kondisi Hindia Belanda waktu itu.16 Dengan begitu maka isi keilmuan hukum yang diberikan di fakultas-fakultas hukum sedikit banyak melanjutkan tradisi Rechtshogeschool tersebut yang merupakan tradisi Eropa Daratan. Tradisi keilmuan ini sebenarnya umurnya sudah sangat tua yang sudah berkembang sejak zaman Romawi Kuno. Namun demikian, semenjak lahirnya Filsafat Positivisme di Eropa, terutama di Perancis, muncul pertanyaan yang bersifat menggugat tentang nilai ilmiah dari Ilmu Hukum itu sendiri. Pertanyaan-pertanyaan itu antara lain mempermasalahkan tentang apakah benar Ilmu Hukum itu memenuhi syarat-syarat sebagai suatu ilmu pengetahuan? Bukankah Ilmu Hukum itu hanya merupakan suatu pengetahuan yang tertib mengenai apa yang merupakan hukum bagi suatu masyarakat pada waktu ini dan di sini, yang mana logika sangat menentukan dalam kegiatan tersebut. Bukankah Ilmu Hukum itu tidak lain hanyalah sebatas sistem berpikir secara tertib tentang apa yang hukum atau hukumnya tanpa ada kaitan tuntutan-tuntutan lain? Tidakkah ilmu hukum itu hanya 15 Bernard Arief Sidharta. 1999. Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, sebuah Penelitian tentang Fondasi kefilsafatan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia. Bandung: Mandar Maju. Hlm. 138. 16 Ibid. Hlm. 171. Bab 1 9 suatu ajaran ‘seni teknik’ apa yang merupakan hukum? artinya seni tentang bagaimana dapat menunjukkan ketentuan atau aturan hukumnya yang pasti bagi masalah-masalah hukum yang konkrit. Dengan demikian Ilmu Hukum itu tidak memenuhi syarat sebagai ilmu (modern). Pendapat yang mencerminkan kritik terhadap Ilmu Hukum pernah dikemukakan oleh von Kirchman dalam tulisannya: “Die Werthlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenchaft” pada tahun 1848. Ia mengemukakan tidak mutunya Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan disebabkan: 1. Kenyataan dalam praktik hukum di masyarakat yang membawa tidak populernya Ilmu Hukum sendiri, terutama di pengadilan. Di situ dapat dilihat berapa banyak jumlah undang-undang yang ada dalam masyarakat, akan tetapi masih saja ada kekosongan-kekosongan. Berapa jumlah pegawai-pegawai yang bertugas di dalam proses peradilan, akan tetapi bagaimana lambatnya beracara di dalam pengadilan untuk mendapatkan hukumnya. Juga betapa telah banyak studi kesarjanaan dalam bidang hukum, akan tetapi juga masih adanya ketidakpastian dan simpang siurnya teori dengan praktik dalam hukum. Itu semua adalah gambaran alam kenyataan dalam praktik hukum. 2. Adanya ketidakpastian dan berubah-ubahnya bahan ilmu hukum, yaitu obyek ilmu hukum itu sendiri. Tidak seperti halnya ilmu fisika, kimia, astronomi, biologi. Ilmu-ilmu ini mempunyai obyek yang pasti dan tidak berubah-ubah. Objek Ilmu Hukum misalnya, lembaga hukum seperti perkawinan, keluarga, negara, hak milik, kontrak dan sebagainya terus menerus berubah. Atas penglihatan yang demikian timbul adanya pertanyaan: jika diperhatikan buku-buku Ilmu Hukum yang begitu besar jumlahnya itu, apakah sebenarnya isi dari segala uraian, komentar, monografi, kumpulan-kumpulan keputusan dan kasus-kasus itu? jawabnya bilamana itu diperiksa dengan seksama maka sembilan persepuluh daripadanya memuat soal kekosongankekosongan dalam undang-undang, ketidakjelasan (kekaburan), memuat kontradisksi-kontradiksi dalam dirinya. Ringkasnya memuat soal-soal tidak benarnya undang-undang, usangnya undang-undang, kesembronoan undang-undang. Itu semua menunjukkan bahwa yang menjadi sasaran atau obyek ilmu hukum adalah ketidakcakapan dari pembentuk undang-undang, sikap memilih satu pihak dari pembentuk undang-undang, dan pula gambaran nafsu pembentuk undang-undang. Pendahuluan 10 3. Hukum itu sendiri ‘adanya’ tidak nyata. Oleh sebab itu hakikat hukum tidak mempunyai ke-ada-an seperti halnya dengan benda-benda dan kejadian-kejadian yang menjadi objek ilmu pengetahuan lainnya. Kaidah hukum bukanlah suatu benda dan kejadian yang dapat ditangkap dengan pancaindera. Kaidah hukum itu adalah suatu ketentuan yang mengharuskan, artinya suatu perintah atau larangan untuk berbuat. Dengan kata lain sasaran Ilmu Hukum itu adalah suatu perintah untuk berbuat secara tertentu. Karena objeknya yang tidak nyata ini maka sulit untuk mengkualifikasikan Ilmu Hukum sebagai Ilmu (modern).17 Pertanyaan-pertanyaan seperti telah disebutkan, menimbulkan keheranan di kalangan ahli hukum sendiri. Bukankah Ilmu Hukum yang berasal dari tradisi Eropa Daratan itu umurnya sudah sangat tua dan mulai berkembang sejak dari Zaman Romawi Kuno, lantas mengapa baru abad ke-19 pertanyaan-pertanyaan itu muncul? Bukankah sebelumnya sudah ada uraian-uraian tentang hukum yang menunjukkan nilai ilmu dari Ilmu Hukum tersebut? Tidakkah karya-karya dari sebelum abad ke-19 itu sudah ilmiah? Misalknya karya Gaius-Justinianus, Hugo de Groot, Blackstone dan lain-lain sarjana hukum sebelum abad ke-19 mempunyai nilai ilmiah yang sangat tinggi? Timbulnya pertanyaan-pertanyaan di atas tidak disebabkan oleh karena orang tidak percaya pada nilai dan mutu karya-karya sarjana hukum yang besar tersebut, akan tetapi lebih disebabkan karena pengaruh alam pikiran filsafat keilmuan yang berkembang saat itu mengenai ukuran apa ilmu itu dan apa tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh pemikiran filsafat tersebut mengenai konsep ilmu. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut maka perlu dikaji secara kritis tentang posisi Ilmu Hukum di tengah munculnya paradigma-paradigma baru. Lahirnya paradigma positivisme dan kemudian dilanjutkan dengan perkembangan paradigma post-postivisme, paradigma critical dan M. Koesnoe. 1981. “Kritik Terhadap Ilmu Hukum”. Makalah Ceramah di Hadapan Para Dosen dan Mahsaiswa Fakultas Hukum UII Yogyakarta. 3-4 Pebruari 1981. Hlm. 6. 17 Bab 1 11 terakhir paradigma construktivisme, semuanya itu membawa dampak pada perkembangan keilmuan hukum. Di sinilah arti pentingnya kajian dalam buku ini dihadirkan yakni untuk mencari posisi yang tepat dari Ilmu Hukum itu sendiri di tengah berkembangnya paradigma keilmuan yang muncul akhir-akhir ini. Hal yang sangat menarik di tengah munculnya berbagai paradigma tersebut adalah munculnya wacana baru tentang Paradigma Islam yang dikembangkan oleh Kuntowijoyo, seorang guru besar sejarah dari Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada sekitar tahun 2000.18 Konsep paradigma tersebut lebih lanjut diperjelas oleh Heddy Shri Ahimsa-Putra yang melahirkan konsep Paradigma Profetik. Gagasan ilmu yang berparadigma Profetik menurut Kuntowijoyo diilhami oleh dua pemikir besar yakni Muhammad Iqbal (seorang pemikir Islam) dan Roger Garaudy (pemikir Perancis yang kemudian masuk Islam). Bagi Ilmu Hukum, munculnya pemikiran profetik ini terasa mendapatkan jiwa dan wadah baru yang patut dikembangkan sebagai local genius pendidikan hukum. Gagasan untuk membangun dan mengembangkan Ilmu Profetik pada awalnya dipicu antara lain oleh perdebatan yang terjadi di kalangan Cendekiawan Islam mengenai teologi yang terjadi pada sebuah seminar di Kaliurang, Yogyakart.19 Terdapat dua kubu yang tidak sepaham, yakni kubu yang berhalauan teologi konvensional dan kubu yang berhalauan teologi transformatif. Kubu konvensional mengartikan teologi sebagai Ilmu Kalam, yaitu suatu disiplin yang mempelajari ketuhanan, bersifat abstrak normatif, dan skolastik, sedangkan kubu teologi transformatif, memaknai teologi sebagai penafsiran terhadap realitas dalam perspektif ketuhanan dan lebih merupakan refleksi-refleksi empiris. Menurut Kuntowijoyo, perbedaan pandangan ini sulit diselesaikan, karena masing-masing memberikan makna yang berbeda Gagasan ini bersamaan dengan munculnya wacana Hukum Progresif yang dibidani oleh Satjipto Rahardjo di Fakultas Hukum Undip Semarang sekitar tahun 2001. 19 Lajnah Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Nahdhatul Ulama DIY. Makalah Seminar Nasional Teologi Pembangunan. Kaliurang 25-26 Juni 1988. 18 Pendahuluan 12 terhadap konsep paling pokok, yaitu konsep teologi itu sendiri. Untuk mengatasi kemacetan dialog ini Kuntowijoyo mengusulkan digantinya istilah teologi menjadi ilmu sosial, sehingga istilah Teologi Transformatif diubah menjadi Ilmu Sosial Transformatif.20 Peristiwa lain yang menjadi pemicu gagasan Kuntowijoyo tentang Ilmu Profetik adalah Kongres Psikologi Islam I di Solo, 10 Oktober 2003. Ketika itu ada pemakaian istilah “islamisasi pengetahuan”, yang menggelisahkan Kuntowijoyo, karena makna istilah tersebut kemudian “diplesetkan” ke arah “islamisasi non-pri”, yang dihubungkan dengan “sunat secara Islam”, atau tetakan (bhs. Jawa). Ia sakit hati dengan penyamaan itu, meskipun ada benarnya juga. Ia sakit hati karena sebuah gerakan intelektual yang sarat nilai keagamaan disamakan dengan gerakan bisnis pragmatis. Oleh karena itu ia tidak lagi memakai istilah “islamisasi pengetahuan”, dan ingin mendorong supaya gerakan intelektual umat sekarang ini melangkah lebih jauh, dan mengganti “islamisasi pengetahuan” menjadi “pengilmuan Islam”. Dari reaktif menjadi proaktif”.21 Kuntowijoyo kemudian menghimpun gagasan-gagasan yang masih terserak di sana-sini menjadi sebuah buku kecil dengan judul: Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika. Menurut Kuntowijoyo, pengembangan Paradigma Islam merupakan langkah pertama dan strategis ke arah pembangunan Islam sebagai sistem dan gerakan sosialbudaya ke arah sistem Islam yang kaffah, modern dan berkeadaban. Dengan demikian Islam akan lebih credible bagi pemeluknya dan juga bagi non-Muslim. Langkah awal ini adalah untuk mewujudkan sebuah Paradigma Islam dalam jagad ilmu, yang sampai saat ini umumnya menggunakan basis paradigma dari dunia barat.22 Kuntowijoyo. 2007. Islam sebagai Ilmu, Epistemologi, Metodologi dan Etika. Jogjakarta: Tiara Wacana. Hlm.83. Baca pula Heddy Shri Ahimsa-Putra, 2011. “Paradigma Profetik sebuah Konsepsi”, Makalah disampaikan dalam Diskusi Pengembangan Ilmu Profetik 2011,diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum - UII, di Yogyakarta, 18 Nopember 2011. 21 Kuntowijoyo. Ibid. Hlm. vii-viii. 22 Ibid. Hlm. ix 20 Bab 1 13 Menurut Thomas Kuhn, bahwa revolusi ilmu tidak lain adalah perubahan paradigma, perubahan pada mode of thought, pada mode of inquiry. Oleh karena itu bahwa inti ilmu itu tidak lain adalah paradigma. Jika demikian, maka apa yang seharusnya dibahas dan dibangun terlebih dahulu adalah sebuah konsepsi atau pandangan mengenai paradigma, mengenai sebuah kerangka pemikiran. Hal ini menurut Ahimsa-Putra, yang belum dilakukan oleh Kuntowijoyo, sehingga pemikirannya mengenai Ilmu Profetik masih jauh dari lengkap. Oleh karena itu perlu dikembangkan lebih lanjut gagasan Kuntowijoyo dalam membangun paradigma profetik yang lebih jelas komponennya, lebih kokoh dasarnya, dan juga lebih jelas sosoknya. Terhadap hal ini Ahimsa-Putra telah mencoba menyusun konsep tentang paradigma yang lebih jelas dan terukur yang menjadi dasar dari konsep paradigma profetik.23 Penjelasan detail tentang hal ini akan diuraikan pada bab 2. Berdasarkan latar belakang dan semangat pencarian seperti itulah, tulisan-tulisan dalam buku ini dimaksudkan untuk menawarkan gagasan tentang perlunya pengembangan Ilmu Hukum yang berparadigma profetik. Bagi Ilmu Hukum sendiri, munculnya pemikiran Ilmu Profetik ini terasa mendapatkan ideologi baru yang patut diwadahi dan kemudian dikembangkan sebagai alternatif kajian ilmu hukum di tengah-tengah situasi transisi dan krisis epistemologi keilmuan, terutama ilmu hukum. Pada tahapan awal hal penting dan mendasar yang perlu dikaji dalam rangka pengembangan ilmu hukum profetik adalah pertanyaan besar dan mendasar yaitu apa yang menjadi landasan kefilsafatan bangunan Ilmu Hukum Profetik dan kemudian bagaimanakah penjabaran basis utama ilmu tersebut menjadi asumsi-asumsi/prinsip-prinsip dasar baik dalam dimensi ontologis, epistemologis maupun aksiologisnya. Landasan kefilsafatan Ilmu Hukum Profetik ini akan diuraikan pada bab-bab berikutnya. 23 Heddy Shri Ahimsa-Putra. 2011. Op.Cit. Pendahuluan 14 C. Apa dan Mengapa Digunakan Istilah Profetik? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah ‘profetik’ diartikan sebagai ‘kenabian’.24 Kata kenabian sendiri berasal dari bahasa Arab ‘nubuwah’ sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an Surat al-Imran (3): 79, artinya: Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab, Hikmah dan Kenabian, lalu Dia berkata kepada manusia: “Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah.” akan tetapi (dia berkata): “Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Kata kenabian memiliki asal kata nabi, yaitu seorang hamba Allah yang diberi kitab, hikmah, kemampuan berkomunikasi dan berintegrasi denganNya, para malaikatNya, serta kemampuan mengimplementasikan kitab dan hikmah itu, baik dalam diri sendiri secara pribadi, maupun umat manusia dan lingkungannya. Sementara kata kenabian mengandung makna segala hal ikhwal yang berhubungan dan berkaitan erat dengan seorang yang telah memperoleh potensi kenabian. Mereka itu adalah Nabi Muhammad SAW, para nabi pada umumnya, dan para ahli waris nabi yaitu aulia, Allah. Namun auliya Allah itu tidak menyampaikan risalah baru kepada umat manusia, akan tetapi mereka sebagai penyambung dan penerus lidah Nabi Muhammad SAW. Artinya mereka bertugas mengembangkan secara luas pesanpesan ketuhanan (wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW) serta pesan-pesan kenabian (Sunnah nabi). Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW, “Ulama itu adalah ahli waris para nabi” (HR.Abu Dawud, Turmudzi, dan Ibnu Majjah dari Abu Darda R.A).25 Mereka yang telah dapat meneruskan perjuangan dan risalah kenabian tersebut adalah mereka yang telah mewarisi potensi kenabian. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1990. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 702. 25 Hamdani Bakran Adz-Dzakiey. 2008. Psikologi Kenabian, Prophetic Psychology Menghidupkan Potensi dan Kepribadian Kenabian dalam Diri. Ctk ketiga. ogyakarta: Al-Manar. Hlm.44. 24 Bab 1 15 Mereka itu mempunyai kemampuan memahami, mengaplikasikan, dan memasukkan ruh dan batin al-Qur’an dan al-Hikmah, sebagai buah dari ketaatan dan kedekatannya dengan Allah SWT dan rasulNya Muhammad SAW serta para nabi-nabiNya. Mereka itulah para ulama billah, yaitu hamba Allah yang dengan ilmu yang dimilikinya merasa takut, tunduk, dan patuh kepadaNya sehingga muncul (tajalli) dan hadir Nur Allah SWT ke dalam eksistensi dirinya sebagaimana para nabi tersebut.26 Penggunaan istilah profetik tidak lepas dari kesinambungan dari penggagas awal istilah tersebut, yakni Muhammad Iqbal dan Roger Garaudy. Dalam buku Membangun Kembali Pikiran Agama dalam Islam (Iqbal,1966:123), Iqbal mengungkapkan tentang peristiwa mi’raj Nabi Muhammad SAW. Seandainya nabi itu seorang mistikus atau sufi, tentu beliau tidak ingin kembali ke bumi lagi, karena telah merasa tenteram dengan Tuhan dan berada di sisiNya. Akan tetapi nabi kembali ke bumi untuk menggerakkan perubahan sosial, untuk mengubah jalannya sejarah. Beliau memulai suatu transformasi sosial budaya, berdasarkan cita-cita profetiknya. Dengan kata lain, pengalaman religius itu justru menjadi dasar keterlibatannya dalam sejarah, suatu aktivisme sejarah. Sunnah nabi berbeda dengan jalan seorang mistikus yang puas dengan pencapaian sendiri. Sunnah nabi yang seperti itu disebutnya Etika Profetik.27 Selanjutnya dari Roger Garaudy, seorang filosuf Perancis yang menjadi muslim, kita mengenal istilah Filsafat Profetik. Menurutnya filsafat barat tidak memuaskan sebab hanya terombang ambing antara dua kubu, idealis dan materialis, tanpa kesudahan. Filsafat barat (filsafat kitis) itu lahir dari pertanyaan: bagaimana pengetahuan itu dimungkinkan. Ia menyarankan agar mengubah pertanyaan itu menjadi: bagaimana wahyu itu dimungkinkan. Dikatakan bahwa satu-satunya cara untuk menghindari kehancuran peradaban ialah dengan mengambil 26 27 Ibid. Hlm. 45. Kuntowijoyo. Op.cit. Hlm. 97. Pendahuluan 16 kembali warisan Islam. Filsafat barat sudah membunuh Tuhan dan manusia. Oleh karena itu ia menganjurkan supaya umat manusia memakai filsafat profetik (kenabian) dari Islam dengan mengakui wahyu (Garaudy, 1982:139-168).28 Dari istilah profetik tersebut kemudian mengilhami Kuntowijoyo untuk menggunakan istilah Ilmu Sosial Profetik. Ilmu ini bertujuan tidak hanya menjelaskan dan mengubah fenomena sosial, sebagaimana ilmuilmu sosial akademis maupun ilmu-ilmu sosial kritis, tetapi juga memberi petunjuk ke arah mana transformasi itu dilakukan, untuk apa, dan oleh siapa. Ilmu Sosial Profetik tidak sekedar mengubah demi perubahan, tetapi mengubah berdasarkan cita-cita etik dan profetik tertentu. Dengan pengertian ini maka Ilmu Sosial Profetik secara sengaja memuat kandungan nilai dari cita-cita perubahan yang didamkan oleh masyarakatnya. Bagi kita itu adalah perubahan yang didasarkan pada cita-cita humanisasi, liberasi, dan transendensi, sebagaimana diderivasi dari dari misi historis Islam sebagaimana terkandung dalam al-Qur’an, khususnya Surat al-Imran (3):110. Engkau adalah umat terbaik yang diturunkan di tengah manusia untuk menegakkan kebaikan, mencegah kemungkaran (kejahatan), dan beriman kepada Allah. Ketiga pilar itulah yaitu amar ma’ruf (ditransformasi menjadi humanisasi), nahi munkar (ditransformasi menjadi liberasi), dan tukminuna billah (ditransformasi menjadi transendensi), yang menjadi muatan nilai Ilmu Sosial Profetik. Dengan kandungan ketiga nilai tersebut, Ilmu Sosial Profetik diarahkan untuk rekayasa masyarakat menuju cita-cita sosial-etiknya di masa depan. Jika dibandingkan, Filsafat Liberalisme di barat lebih mementingkan pada yang pertama (humanisasi), Maxisme lebih mementingkan yang kedua (liberasi), dan kebanyakan agama lebih mementingkan yang ketiga (transendensi). Ilmu Sosial Profetik mencoba untuk menggabungkan ketiganya, yang satu tidak terpisah dari lainya.29 28 29 Kuntowijoyo. Op.cit. Hlm. 98. Kuntowijoyo. Op.cit. Hlm. 99. Bab 1 17 Amar ma’ruf dalam bahasa sehari-hari dapat berarti apa saja, dari yang sangat individual seperti berdoa, berzikir, dan shalat, sampai yang semi sosial seperti menghormati orang tua, menyambung persaudaraan, menyantuni anak yatim, serta yang bersifat kolektif seperti mendirikan clean government, mengusahakan jamsostek, dan membangun sistem keamanan sosial. Untuk itu dipakai kata humanisasi. Dalam Bahasa latin, humanitas berarti ‘makhluk manusia’, ‘kondisi menjadi manusia’, jadi humanisasi berarti memanusiakan manusia; menghilangkan ‘kebendaan’, ketergantungan, kekerasan dan kebencian dari manusia. Jadi tujuan humanisasi adalah untuk memanusiakan manusia. Kita tahu bahwa sekarang mengalami proses dehumanisasi, karena masyarakat industri kita menjadikan kita sebagai bagian dari masyarakat abstrak tanpa wajah kemanusiaan. Kita mengalami objektivasi ketika berada di tengah-tengah mesin-mesin politik dan mesin-msein pasar.Ilmu dan teknologi juga telah membantu kecenderungan reduksionistik yang melihat manusia dengan cara parsial.30 Nahi munkar dalam bahasa sehari-hari dapat berati apa saja, dari mencegah teman mengkonsumsi ectacy, melarang carok, memberantas judi, menghilangkan lintah darat, sampai membela nasib buruh dan mengusir penjajah. Untuk itu digunakan kata liberasi (bahasa Latin liberare berarti ‘memerdekakan’) artinya ‘pembebasan’ semuanya dengan konotasi yang mempunyai signifikansi sosial. Jadi tujuan liberasi adalah pembebasan dari kekejaman kemiskinan struktural, keangkuhan teknologi, dan pemerasan kelimpahan. Kita menyatu rasa dengan mereka yang miskin, mereka yang terperangkap dalam kesadaran teknokratis, dan mereka yang tergusur oleh ekonomi raksasa. Kita ingin bersama-sama membebaskan diri dari belenggu-belenggu yang kita bangun sendiri.31 Tukminuna billah yang terdapat dalam al-Quran digunakan padanan kata yang umum yaitu transendensi (bahasa Latin trancendere berati 30 31 Kuntowijoyo. Op.Cit. Hlm. 88 Loc.Cit. Pendahuluan 18 naik ke atas, bahasa Inggris to transcend adalah menembus, melewati, melampaui) artinya ‘perjalanan yang di atas atau di luar’. Kata ini meliputi istilah sehari-hari (misalnya orang yang kelewat-lewat kuatnya seperti Superman, altruisme mengatasi individualisme), sastra transendental (sastra yang mencoba mencari realitas spiritual di balik gejala-gejala), filsafat transendental (misalnya kantianisme yang percaya pada pengetahuan a priori di luar pengalaman), segala supernatural (misalnya ESP, Extra Sensory Perception) dan TM (transcendental Meditation), dan istilah teologis (misalnya soal ketuhanan, makhluk-makhluk gaib). Istilah teologislah yang dimaksud dengan transendensi. Jadi tujuan transendensi adalah menambahkan dimensi transendental dalam kebudayaan. Kita sudah banyak menyerah pada arus hedonisme, materialisme, dan budaya dekaden. Kita percaya bahwa sesuatu harus dilakukan, yaitu membersihkan diri dengan mengingatkan kembali diemnsi transendental yang menjadi bagian sah dari fitrah kemanusiaan. Kita ingin meraskan kembali dunia ini sebagai rahmat Tuhan. Kita ingin hidup kembali dalam suasana yang lepas dari ruang dan waktu, ketika kita bersentuhan dengan kebsaran Tuhan.32 Digunakannya istilah profetik yang kemudian dipakai dalam nomenklatur buku ini berjudul IlMU HUKUM PROFETIK, pertamatama adalah untuk memberikan tanda perbedaan secara formal dan material antara Ilmu Hukum yang umum atau konvensional dengan yang profetik. Dari tanda perbedaan formal itu, kemudian kita dapat masuk ke dalam perbedaan-perbedaan yang lebih substansial tentang isi konsep dari kedua ilmu hukum tersebut. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa Ilmu Hukum yang umum atau konvensional adalah ilmu hukum yang jika dilihat dari sejarah kelahirannya adalah yang lahir di Eropa Barat yang cikal bakalnya berasal dari Peradaban Yunani dan Romawi Kuno yang menganut filsafat rasionalisme murni. Filsafat ini pada sekitar abad pertengahan telah melahirkan Filsafat Epistemogi dengan ciri pokoknya adalah 32 Loc.Cit Bab 1 19 menanggalkan sama sekali paham ketuhanan dan agama (sekularantroposentris). Sumber pengetahuan satu-satunya yang dianggap valid dalam menjelaskan totalitas (termasuk hukum) adalah pikiran manusia itu sendiri, baik yang ideal maupun empiris. Di luar itu tidak diakui. Konsekuensinya di bidang pengetahuan hukum pun tidak diakui adanya hukum-hukum yang bersumber dari tuhan atau hukum agama dan hanya diakui sebagai valid adalah hukum-hukum yang dibentuk dan bersumber dari pikiran manusia belaka. Cara berpikir dan berhukum yang seperti itu telah melahirkan krisis epistemologi ilmu, termasuk juga ilmu hukum. Kondisi ini telah melahirkan cara berilmu dan berhukum yang materialistik dan atheistik. Cara berilmu dan berhukum yang demikian tentunya akan membawa bahaya yaitu menyesatkan peradaban umat manusia dan tentunya kita mempunyai kewajiban untuk mencegahnya dan mencari upaya-upaya alternatif solusinya. Di sinilah arti penting Ilmu Hukum Profetik itu dihadirkan. D. Sistematika dan Diskripsi Muatan Isi Buku Buku ini mencoba meramu gagasan tentang Ilmu Hukum Profetik, yang dasar-dasar asumsi keilmuannya diturunkan dari Paradigma Profetik. Upaya ini masih sebatas pada tahapan pencarian dan uji coba dari aspek Filsafat Ilmu Hukum. Oleh karena itu uraian tentang sistematikanya belum menunjukkan hal yang runtut dan sistematis. Muatan isinya pun belum menunjukkan hal yang mantap, utuh dan komprehensif serta terkesan masih bersifat meraba-raba. Terkadang terjadi locatan-loncatan gagasan yang kurang sambung sehingga pengorganisasian ide-idenya belum mengalir secara logis dan bahkan kadang terputus. Ini semua kami sadari karena buku ini masih dalam tataran gagasan awal dan pencarian rumusan. Di sisi lain buku ini berupa bunga rampai dari berbagai tulisan, dan itulah umumnya kelemahan buku yang berupa bunga rampai, bukan merupakan gagasan yang utuh dan sistematis. 20 Pendahuluan Untuk memudahkan pembacaan, buku ini disusun menjadi 6 (enam) bab. Pada bab 1, dipaparkan tentang permasalahan umum hubungan ilmu pengetahuan dan agama (kepercayaan) pada zaman kuno, pertengahan dan modern, baik yang terjadi pada masyarakat Eropa maupun masyarakat Muslim pada umumnya. Pada intinya ingin mengemukakan bahwa dalam tradisi peradaban Islam tidak ada sama sekali konfik antara agama dan ilmu pengetahuan. Justru ajaran atau doktrin Islam itu sendiri sangat mendorong orang Islam untuk mencari ilmu pengetahuan (hukumnya wajib ‘ain), Nabi Muhammad sendiri mendorong umatnya untuk mencari ilmu sampai ke negeri China sekalipun (Hadits). Seperti diketahui bahwa China pada waktu itu belum sama sekali terjamah oleh ajaran Islam. Sebaliknya dalam tradisi peradaban barat terjadi konflik berdarah antara agama dan Ilmu pengetahuan, sehingga berdampak pada hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan tidak harmonis. Pada bab ini juga dipaparkan adanya krisis epistemologis keilmuan (termasuk ilmu hukum) yang terjadi di dunia barat yang mendorong kaum muda muslim (Indonesia) untuk mendekonstruksi paradigma keilmuan yang berkembang di dunia barat. Di sini ditawarkan paradigma baru yang disebut Paradigma Profetik, yang gagasan awalnya ditebarkan oleh Kuntowijoyo. Dari payung paradigma itulah digagas tentang Ilmu Hukum Profetik. Pada bab 2 dipaparkan tentang konsep paradigma profetik. Konsep ini pada awalnya digagas oleh Kuntowijoyo, namun menurut Heddy Shri Ahima-Putra isi konsepnya masih jauh dari lengkap. Untuk melengkapi isi konsepnya, Ahimsa-Putra mencoba memberikan definisi konsep, menguraikan unsur-unsurnya, skemanya, basis epistemologis paradigma profetik, asumsi dasar tentang basis pengetahuan, asumsi dasar tentang obyek material, asumsi dasar tentang obyek yang diteliti, asumsi dasar tentang ilmu pengetahuan, asumsi dasar tentang ilmu alam atau sosial profetik, Asumsi dasar tentang dispilin profetik, Etos paradigma profetik, Model paradigma profetik, dan Implikasi Epistemogi Profetik. Dengan demikian konsep tentang paradigma Bab 1 21 profetik ini menjadi lebih jelas komponennya lebih kokoh dasarnya, dan juga lebih jelas sosoknya. Paradigma profetik ini merupakan induk atau payung yang menaungi dan menjadi pendasar lahirnya Ilmu-Ilmu Profetik, termasuk di dalamnya Ilmu Hukum Profetik. Oleh karena itu isi uraiannya bersifat hal-hal yang sangat mendasar. Pada bab 3 diuraikan tentang landasan ontologi ilmu hukum profetik. Landasan ontologis di sini dibutuhkan dan dimaksudkan untuk memahami bangunan ilmu dari aspek obyek material yang menjadi sasaran pemikiran atau kajian ilmu tersebut. Obyek kajian di sini dapat diperinci menjadi obyek kajian material dan formal. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa setiap disiplin ilmu pasti mempunyai obyek kajian masing-masing baik terkait dengan obyek material maupun obyek formal. Obyek material terkait dengan hakikat realitas yang dikaji atau diteliti atau sasaran pemikiran. Hal ini dapat mencakup hal-hal yang konkrit maupun abstrak dari suatu realitas seperti ide-ide dan nilainilai. Sementara itu obyek formal terkait dengan sudat pandang orang melihat obyek material atau realitas yang dikaji serta prinsip-prinsip yang digunakan. Obyek formal ini dapat melahirkan berbagai pendekatan yang berbeda-beda sehingga melahirkan aliran-aliran dalam setiap disiplin keilmuan. Kedua obyek tersebut akan membingkai pada berbagai kajian dan penelitian dari displin ilmu tersebut. Pada landasan ontologi Ilmu Hukum Profetik ini pertanyaan mendasar yang muncul dan perlu dijelaskan adalah apa hakikat dari realitas yang disebut hukum menurut perspektif paradigma profetik?. Jawaban atas pertanyaan ini tentunya harus dimulai dengan mengemukakan asumsi atau anggapan dasar (basis assumption) apa yang dimaksud dengan hukum itu. Asumsi atau anggapan dasar adalah pandangan-pandangan mengenai suatu hal, yaitu hukum yang tidak dipertanyakan lagi kebenarannya atau sudah diterima kebenarannya. Pandangan ini merupakan titik-tolak atau dasar bagi upaya memahami dan menjawab suatu persoalan, karena pandangan-pandangan tersebut dianggap benar atau diyakini kebenarannya. Anggapan-anggapan ini 22 Pendahuluan bisa lahir dari (a) perenungan-perenungan filosofis dan reflektif, bisa dari (b) penelitian-penelitian empiris yang canggih, bisa pula dari (c) pengamatan yang seksama. Asumsi dasar dibutuhkan agar kita mempunyai titik berdiri (standing point) pemikiran kita tentang hakikat hukum itu. Tanpa asumsi dasar kita akan kesulitan dan mungkin menjadi bingung memahami tentang hukum dan segala persoalan yang terkait dengannya. Pada bab 4 diuraikan tentang landasan epistemologi ilmu hukum profetik. Landasan epistemologi ilmu dibutuhkan terkait dengan cara bagaimana kebenaran dari pengetahuan itu diperoleh secara valid dan terpercaya berdasarkan suatu metode ilmiah tertentu. Melalui epistemologi tersebut kita dapat memahami bagaimana ilmu itu ada atau lahir dan diyakini kebenarannya secara ilmiah. Melalui epistemologi itu juga kita dapat membedakan mana pengetahuan yang disebut ilmu dan yang bukan ilmu, mana yang ilmiah dan mana yang tidak ilmiah. Dalam epistemologi ilmu, hal mendasar yang menjadi pertanyaan kefilsafatan adalah bagaimana proses yang memungkinkan diperolehnya pengetahuan yang disebut ilmu? Bagaimana prosedurnya? Hal-hal apa yang harus diperhatikan agar kita mendapatkan pengetahuan yang benar? Apa yang disebut kebenaran itu sendiri? Apa kriterianya? Cara/teknik/ sarana apa yang membantu kita dalam mendapatkan penegathuan yang berupa ilmu? Pada bab ini diuraikan berturut-turut tulisan yang membahas tentang basis epistemologis ilmu-ilmu profetik yang ditulis oleh M.Syamsudin. Selanjutnya menguraikan tentang Meninjau Pemikiran Ilmu, Ilmiah Modern dan dasar Filsafatnya Dewasa Ini, Suatu Tinjauan dalam Rangka Persepektif wawasan Ajaran Ke-Islaman, oleh M. Koesnoe. Pada bagian pertama diuraikan tentang dasar-dasar keilmuan modern (barat) beserta filsafat yang mendasarinya. Pada bagian yang pertama ini pada intinya berisi kritik terhadap epistemologi keilmuan barat yang bersifat sekuler. Pada bagian yang kedua diuraikan tentang tinjauan dari perspektif wawasan ajaran ke-Islaman, yang mengambil model Pemikiran Imam Al-Ghozali. Selanjutnya dibahas tentang Paradigma Bab 1 23 Profetik dalam Hukum Islam Melalui Pendekatan Systems, Oleh Amin Abdullah. Pada bab 5 diuraikan tentang landasan aksiologi ilmu hukum profetik. Landasan aksiologi ini dibutuhkan untuk memahami persoalanpersoalan keilmuan yang berkaitan dengan pengembanan hukum (rechtsbeoefening). Hal mendasar yang menjadi perhatian uraian ini adalah kondisi pengembanan hukum (rechtsbeoefening) di Indonesia, baik pengembangan teoretis maupun praktis, banyak sekali dimensi aksiologis yang perlu untuk mendapat pencerahan. Pengembanan hukum adalah kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum di dalam masyarakat. Kegiatan tersebut mencakup kegiatan membentuk, melaksanakan, menerapkan, menemukan, meneliti, dan secara sistematikal mempelajari dan mengajarkan hukum yang berlaku. Pengembanan hukum itu dapat dibedakan pengembanan hukum teoretis dan praktis. Bab 6 adalah bab terakhir yang muatanya berisi pertama-tama tentang peluang untuk mengembangkan Hukum Profetik di Era Postmodern, selanjutnya diuraikan tentang simpulan tentang landasan kefilsafatan Ilmu Hukum Profetik yang telah diuraikan dan dibahas pada bab-bab sebelumnya. 24 Pendahuluan BAB 2 PARADIGMA PROFETIK (Sebuah Konsepsi)1 Oleh Heddy Shri Ahimsa-Putra A. Pengantar Kata profetik berasal dari bahasa Inggris ‘prophet’, yang berarti nabi. Menurut Ox-ford Dictionary ‘prophetic’ adalah (1) “Of, pertaining or proper to a prophet or prophecy”; “having the character or function of a prophet”; (2) “Characterized by, containing, or of the nature of prophecy; predictive”. Jadi, makna profetik adalah mempunyai sifat atau ciri seperti nabi, atau bersifat prediktif, memrakirakan. Profetik di sini dapat diterjemahkan menjadi ‘kenabian’. Pertanyaannya kemudian adalah: adakah ilmu kenabian atau paradigma kenabian? Ilmu atau paradigma seperti apa ini? Gagasan mengenai ilmu profetik di Indonesia -seingat saya- pada mulanya berasal dari Prof. Dr. Kuntowijoyo, guru besar sejarah dari Fakultas Ilmu Budaya, UGM. Gagasan ini dituangkan dalam bukunya yang berjudul Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika, diterbitkan tahun 2004. Meskipun demikian, pemikiran-pemikiran Kuntowijoyo -yang selanjutnya akan saya sebut Mas Kunto, sapaan Makalah ini pernah disampaikan pada “Diskusi Berseri Membangun Paradigma Ilmu Hukum Profetik” diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSH FH UII) Yogyakarta, pada tanggal 18 Nopember 2011. 1 26 Paragima Profetik... akrab saya untuk beliau- mengenai ilmu profetik tersebut bibit-bibitnya sudah ditebar lebih awal dalam bukunya Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi (Mizan, 1991). Apa yang digagas oleh mas Kunto pada dasarnya bukanlah hal yang sama sekali baru dalam jagad pemikiran Islam. Dari tulisan-tulisannya dapat ditemukan tokoh-tokoh pemikir Islam yang banyak mempengaruhi dan memberikan inspirasi pada mas Kunto. Mas Kunto menulis bahwa “Asal-usul dari pikiran tentang Ilmu Sosial Profetik itu dapat ditemukan dalam tulisan-tulisan Muhammad Iqbal dan Roger Garaudy”. Muhammad Iqbal adalah tokoh pemikir Islam, sedang Roger Garaudy adalah ahli filsafat Prancis yang masuk Islam. Mas Kunto banyak mengambil gagasan dua pemikir untuk mengembangkan apa yang diangan-angankannya sebagai ilmu-ilmu profetik, lebih khusus lagi ilmu sosial profetik, karena mas Kunto adalah seorang sejarawan, seorang ilmuwan sosial. Dikatakan oleh mas Kunto bahwa gagasan mengenai ilmu sosial profetik yang dikemukakannya dipicu antara lain oleh perdebatan yang terjadi di kalangan cendekiawan Islam mengenai teologi, yang terjadi dalam sebuah seminar di Kaliurang, Yogyakarta. Saat itu ada dua kubu yang berseberangan pendapat di situ, yakni kubu teologi konvensional, yang mengartikan teologi sebagai ilmu kalam, “yaitu suatu disiplin yang mempelajari ilmu ketuhanan, bersifat abstrak normatif, dan skolastik” dengan kubu teologi transformatif, yang memaknai teologi sebagai “penafsiran terhadap realitas dalam perspektif ketuhanan. Jadi lebih merupakan refleksi-refleksi empiris”. Menurut mas Kunto, perbedaan pandangan ini sulit diselesaikan, karena masing-masing memberikan makna yang berbeda terhadap konsep paling pokok di situ, yaitu konsep teologi itu sendiri. Untuk mengatasi kemacetan dialog ini Kuntowijoyo mengusulkan digantinya istilah teologi menjadi ilmu sosial, sehingga istilah Teologi Transformatif diubah menjadi Ilmu Sosial Transformatif. Peristiwa lain yang menjadi pemicu gagasan mas Kunto tentang ilmu profetik adalah Kongres Psikologi Islam I di Solo, 10 Oktober 2003. Ketika itu ada pemakaian istilah “Islamisasi pengetahuan”, yang Bab 2 27 menggelisahkan mas Kunto, karena makna istilah tersebut kemudian “diplesetkan” ke arah “Islamisasi non-pri”, yang dihubungkan dengan “sunat secara Islam”, atau tetakan (bhs.Jawa). “Tentu saja saya sakit hati dengan penyamaan itu, meskipun ada benarnya juga” begitu tulisa mas Kunto,”Saya sakit hati karena sebuah gerakan intelektual yang sarat nilai keagamaan disamakan dengan gerakan bisnis pragmatis. Oleh karena itu saya tidak lagi memakai istilah “Islamisasi pengetahuan”, dan ingin mendorong supaya gerakan intelektual umat sekarang ini melangkah lebih jauh, dan mengganti “Islamisasi pengetahuan” menjadi “Pengilmuan Islam”. Dari reaktif menjadi proaktif” (2006: vii-viii). Mas Kunto kemudian menghimpun gagasan-gagasan yang masih terserak di sana-sini menjadi sebuah “nonbuku darurat”, “nonbuku comat-comot” -begitu dia menyebut buku kecilnya- yang diberi judul Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika. Menurut mas Kunto “Pengembangan Paradigma Islam itu merupakan langkah pertama dan strategis ke arah pembangunan Islam sebagai sistem, gerakan sosialbudaya ke arah sistem Islam yang kaffah, modern dan berkeadaban. Dengan demikian Islam akan lebih credible bagi pemeluknya dan bagi non-Muslim…” (2006: ix). Apa yang mas Kunto lakukan adalah sebuah langkah awal untuk mewujudkan sebuah Paradigma Islam dalam jagad ilmu pengetahuan, yang sampai saat ini umumnya menggunakan basis paradigma dari dunia Barat. Jika kita sepakat dengan Thomas Kuhn bahwa revolusi ilmu pengetahuan tidak lain adalah perubahan paradigma, perubahan pada mode of thought, pada mode of inquiry, maka kita akan sampai pada pendapat bahwa inti ilmu pengetahuan tidak lain adalah paradigma (Ahimsa-Putra, 2007). Jika demikian, maka apa yang seharusnya dibahas dan dibangun terlebih dahulu oleh mas Kunto adalah sebuah konsepsi atau pandangan mengenai paradigma, mengenai sebuah kerangka pemikiran. Oleh karena ini belum dilakukan oleh mas Kunto, maka dengan sendirinya pemikiran mas Kunto mengenai ilmu profetik masih jauh dari lengkap. 28 Paragima Profetik... Dalam makalah ini saya mencoba mengembangkan lebih lanjut gagasan mas Kunto untuk membangun paradigma profetik yang lebih jelas komponennya lebih kokoh dasarnya, dan juga lebih jelas sosoknya. Tentu saja, karena terbatasnya ruang di sini, tidak semua komponen paradigma profetik akan saya ulas. Bagian yang akan saya ulas terutama adalah bagian tentang epistemologi. B. Paradigma: Apa itu? Sebelum istilah paradigma menjadi sebuah konsep yang populer, para ilmuwan sosial-budaya telah menggunakan beberapa konsep lain dengan makna yang kurang lebih sama, yakni: kerangka teoretis (theoretical framework), kerangka konseptual (con-ceptual framework), kerangka pemikiran (frame of thinking), orientasi teoritis (theoretical orientation), sudut pandang (perspective), atau pendekatan (approach). Kini istilah paradigma sudah mulai banyak digunakan oleh ilmuwan sosialbudaya. Meskipun begitu, istilah-istilah lama tersebut juga tetap akan digunakan di sini, dengan makna yang kurang-lebih sama dengan paradigma (paradigm). Penggunaan konsep paradigma yang semakin lazim kini tidak berarti bahwa makna konsep tersebut sudah jelas atau telah disepakati bersama. Thomas Kuhn (1973) telah berbicara panjang lebar tentang pergantian paradigma, namun sebagaimana telah kita lihat, dia sendiri tidak menjelaskan secara khusus dan rinci tentang apa yang dimaksudnya sebagai paradigma, dan tidak menggunakan konsep tersebut secara konsisten dalam tulisan-tulisannya. Hal ini tampaknya merupakan akibat tidak langsung dari topik pembahasannya, yakni pergantian paradigma dalam ilmu-ilmu alam (Ahimsa-Putra, 2007). Kuhn tidak menyinggung tentang ilmu-ilmu sosial-budaya. Ada kemungkinan ka-rena dia merasa tidak perlu membedakan dua jenis ilmu pengetahuan tersebut, mengingat dua-duanya adalah ilmu pengetahuan. Ada kemungkinan pula karena dia menganggap ilmu sosial-budaya belum merupakan ilmu pengetahuan (science), karena dari perspektif tertentu Bab 2 29 status sains (ilmu) memang belum berhasil dicapai oleh cabang ilmu tersebut (Kuhn, 1977). Kelalaian Kuhn untuk menjelaskan secara rinci apa yang dimaksudnya sebagai paradigma telah menyulitkan kita. Untuk mengatasi kesulitan ini saya mencoba di sini memaparkan apa yang saya maksud dengan paradigma. 1. Paradigma: Sebuah Definisi2 Paradigma -menurut hemat saya- dapat didefinisikan sebagai seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan dan menjelaskan kenyataan dan/ atau masalah yang dihadapi. Berikut adalah penjelasan frasa-frasa dalam definisi ini. “Seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis membentuk suatu kerangka pemikiran.....” Kata “seperangkat” menunjukkan bahwa paradigma memiliki sejumlah unsur-unsur, tidak hanya satu unsur. Unsur-unsur ini adalah konsep-konsep. Konsep adalah istilah atau kata yang diberi makna tertentu. Oleh karena itu, sebuah paradigma juga merupakan kumpulan makna-makna, kumpulan pengertian-pengertian. Kumpulan konsepkonsep ini merupakan sebuah kesatuan, karena konsep-konsep ini berhubungan secara logis, yakni secara paradigmatik, sintagmatik, metonimik dan metaforik sehingga dapat dikatakan sebagai “seperangkat konsep”, seperti halnya peralatan pada orkestra gamelan atau unsur-unsur pada pakaian, yang membentuk seperangkat gamelan dan seperangkat pakaian. Tentu, relasi-relasi pada gejala-gejala empiris ini tidak sama dengan relasi-relasi antar unsur dalam paradigma. Relasi antar unsur dalam paradigma berada pada tataran logika, pada tataran Uraian mengenai paradigma ini saya ambil dari makalah saya di tahun 2009 (AhimsaPutra, 2009). 2 30 Paragima Profetik... pemikiran, sedang relasi antar unsur pada perangkat pakaian dan gamelan berada pada tataran fungsi, atau bersifat fungsional. Selanjutnya, karena makna dan hubungan antar-makna ini adanya dalam pikiran, maka kumpulan konsep yang membentuk kerangka itu disebut juga sebagai kerangka pemikiran. “.....yang berfungsi untuk memahami dan menjelaskan kenyataan dan/ atau masa-lah yang dihadapi”. Dalam pikiran manusia, kerangka pemikiran ini digunakan untuk tujuan tertentu, sehingga kerangka pemikiran ini memiliki fungsi, yakni untuk memahami kenyataan, mendefinisikan kenyataan, menentukan kenyataan yang dihadapi, menggolongkannya ke dalam kategorikategori, dan kemudian menghubungkannya dengan definisi kenyataan lainnya, sehingga terjalin relasi-relasi pada pemikiran tersebut, yang kemudian membentuk suatu gambaran tentang kenyataan yang dihadapi. Kenyataan yang dihadapi menimbulkan berbagai akibat atau reaksi dalam pikiran manusia. Salah satu di antaranya adalah pertanyaanpertanyaan atau rasa tidak puas karena kenyataan yang dihadapi tidak dapat dipahami dengan menggunakan kerang-ka pemikiran yang telah ada, atau kurang sesuai dengan yang diharapkan. Pertanyaan dan ketidakpuasan ini selanjutnya mendorong manusia untuk menjawab pertanyaan tersebut atau mencari jalan guna mengatasi ketidakpuasan yang ada dalam dirinya. Ini berarti bahwa paradigma tidak hanya ada di kalangan ilmuwan saja, tetapi juga di kalangan orang awam, di kalangan semua orang, dari semua golongan, dari se-mua lapisan, dari semua kelompok, dari semua sukubangsa. Meskipun demikian, hal itu berarti bahwa setiap orang menyadari kerangka pemikirannya sendiri. Bahkan, se-bagian besar orang sebenarnya tidak menyadari betul atau tidak mengetahui seperti apa kerangka pemikiran yang dimilikinya, yang digunakannya untuk memahami situa-si dan kondisi kehidupan sehari-hari. Kesadaran ini hanya dapat muncul dari kalangan mereka Bab 2 31 yang dapat melakukan refleksi atas apa yang mereka pikirkan sendiri, yang mengetahui dan dapat menggunakan metode-metode dan prosedur yang harus digunakan dalam proses refleksi tersebut. Bagi upaya pengembangan dan pembuatan paradigma baru, pendefinisian konsep paradigma saja belum cukup. Lebih penting daripada pendefinisian adalah penentuan unsur-unsur yang tercakup dalam pengertian paradigma. Definisi di atas belum memberikan keterangan lebih lanjut tentang isi dari kerangka pemikiran itu sendiri. “Seperangkat konsep” barulah sebuah gambaran umum tentang isi dari kerangka pemikiran tersebut, sedang kenyataannya konsepkonsep ini tidak sama kedudukan dan fungsi-nya dalam kerangka pemikiran dan karena itu juga memiliki nama yang berbeda-beda. Oleh karena itu diperlukan penjelasan lebih lanjut tentang komponenkomponen kon-septual yang membentuk kerangka pemikiran atau paradigma tersebut. Berbagai pembahasan tentang paradigma di kalangan ilmuwan Barat berada di seputar masalah (a) konsepsi tentang paradigma; (b) ada tidaknya paradigma dalam sua-tu disiplin tertentu, dan (c) unsurunsur paradigma. Sayangnya, dari berbagai pemba-hasan itu tidak berhasil dicapai sebuah kesepakatan tentang definisi yang cukup praktis dan strategis mengenai paradigma. Apalagi kesepakatan mengenai unsur-unsur paradigma. Akibatnya, kita mengalami kesulitan untuk memanfaatkan rintisan pemikiran yang dilontarkan oleh Kuhn. Untuk itu kita perlu membangun sebuah konsepsi (pandangan) tentang paradigma, yang berisi bukan hanya definisi, tetapi juga elemen-elemen pokok yang terdapat dalam sebuah paradigma. Dari berbagai kelemahan dan kelebihan gagasan-gagasan tentang paradigma yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan Barat (lihat Ahimsa-Putra, 2008; 2009), saya mencoba di sini untuk mengemukakan gagasan saya tentang paradigma, yang menca-kup definisi dan unsurunsur pokok yang terdapat di dalamnya. Konsepsi tentang paradigma ini saya bangun setelah saya menelaah secara kritis berbagai buku dan 32 Paragima Profetik... artikel para ilmuwan Barat (karena dari Indonesia saya tidak menemukan pembahasan-pembahasan ini) mengenai paradigma, baik yang teoritis, filosofis maupun yang aplikatif. Pertanyaan pokok saya ketika itu adalah: apa yang dimaksud dengan paradigma? apa saja komponen-komponen konseptual atau unsur-unsur pemikiran yang memben-tuk sebuah paradigma dalam sebuah cabang ilmu pengetahuan, terutama ilmu sosial-budaya, dan lebih khusus lagi antropologi budaya? 2. Unsur-unsur (komponen-komponen) Paradigma Sebuah perspektif dalam ilmu sosial-budaya biasanya dapat dibedakan satu sama lain atas dasar asumsi-asumsi atau anggapananggapan dasarnya tentang obyek yang diteliti, masalah-masalah yang ingin dijawab atau diselesaikan, konsep-konsep, meto-de-metode serta teori-teori yang dihasilkannya. Pendapat yang dilontarkan oleh Cuff dan Payne (1980:3) ini merupakan pendapat yang dapat membawa kita kepada pema-haman tentang paradigma dalam ilmu sosial-budaya. Dalam pendapat ini tersirat pan-dangan bahwa sebuah perspektif atau pendekatan -Cuff dan Payne tidak menyebutnya sebagai “paradigma”memiliki sejumlah unsur, di antaranya adalah: asumsi dasar (ba-sic assumption -Cuff dan Payne menyebutnya bedrock assumption-, konsep, metode, pertanyaan dan jawaban-jawaban yang diberikan. Jika “perspektif” adalah juga “paradigma”, maka unsur-unsur tersebut dapat dikata-kan sebagai unsur-unsur paradigma. Meskipun demikian, menurut saya, pandangan Cuff dan Payne tentang unsurunsur perspektif tersebut masih belum lengkap. Masih ada elemen lain yang juga selalu ada dalam sebuah paradigma ilmu sosial-budaya, namun belum tercakup di dalamnya, misalnya model. Selain itu, unsur metode juga masih perlu dirinci lagi. Cuff dan Payne juga masih belum menjelaskan bagaimana ki-ra-kira urut-urutan unsur-unsur tersebut dalam sebuah paradigma atau kerangka ber-fikir tertentu, sehingga posisi masing-masing unsur terhadap yang lain tidak kita keta-hui. Lebih Bab 2 33 dari itu, Cuff dan Payne juga tidak selalu menjelaskan makna dari konsep-konsep yang digunakannya secara rinci, sehingga kita tidak selalu dapat mengetahui dengan baik apa yang dimaksudkannya. Sebuah paradigma, kerangka teori atau pendekatan dalam ilmu sosial-budaya me-núrut hemat saya terdiri dari sejumlah unsur pokok, yakni: (1) asumsi-asumsi dasar; (2) nilai-nilai; (3) masalah-masalah yang diteliti (4) model; (5) konsep-konsep; (6) metode penelitian; (7) metode analisis; (8) hasil analisis atau teori dan (9) representasi (etno-grafi) (Ahimsa-Putra, 2009). Berikut ini adalah uraian mengenai komponen-komponen paradigma ini, yang menurut saya perlu diberikan. a. Asumsi-asumsi/Anggapan-anggapan (Basic Assumptions) - (1) Dasar Asumsi atau anggapan dasar adalah pandangan-pandangan mengenai suatu hal (bisa benda, ilmu pengetahuan, tujuan sebuah disiplin, dan sebagainya) yang tidak di-pertanyakan lagi kebenarannya atau sudah diterima kebenarannya. Pandangan ini merupakan titik-tolak atau dasar bagi upaya memahami dan menjawab suatu persoalan, karena pandangan-pandangan tersebut dianggap benar atau diyakini kebenarannya. Anggapan-anggapan ini bisa lahir dari (a) perenunganperenungan filosofis dan reflektif, bisa dari (b) penelitian-penelitian empiris yang canggih, bisa pula dari (c) pengamatan yang seksama. Jika asumsi ini berasal dari pandangan filosofis dan reflektif, pandangan ini biasanya lantas mirip dengan ‘ideologi’ si ilmuwan, dan ini tentu saja bersifat subyektif. Oleh karena itu, muncul kini pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada “obyektivitas” dalam ilmu sosialbudaya, sebab apa yang selama ini dianggap sebagai “obyektivitas” ternyata juga didasarkan pada asumsi-asumsi filosofis tertentu, yang tidak berbeda dengan ‘ideologi’. Asumsi-asumsi dasar biasanya terlihat dengan jelas dalam rumusan-rumusan tentang hakikat sesuatu atau definisi mengenai sesuatu, dan ini biasanya merupakan jawaban atas pertanyaan “Apa itu...?”. Misalnya saja, “Apa itu kebudayaan?”; “Apa itu masyarakat?”; “Apa itu karya sastra?”, dan sebagainya. Dalam dunia Paragima Profetik... 34 ilmu pengetahuan definisi mengenai sesuatu inilah yang akan sangat menentukan langkah-langkah kegiatan ilmiah selanjutnya. Dari paparan di atas terlihat bahwa asumsi-asumsi dasar merupakan fondasi dari sebuah disiplin atau bidang keilmuan, atau dasar dari sebuah kerangka pemikiran, dan seperti halnya fondasi sebuah gedung yang tidak terlihat, demikian pula halnya dengan asumsi dasar. Suatu kerangka teori dalam ilmu sosial-budaya biasanya mempunyai banyak asumsi dasar. Akan tetapi, tidak semua asumsi dasar ini selalu dikemukakan secara eksplisit. Bahkan kadang-kadang malah tidak dipaparkan sama sekali, karena semua orang dianggap telah mengetahuinya. Mengapa digunakan istilah ‘asumsi’, bukan ‘dalil’ atau ‘hukum’, jika memang kebenarannya sudah tidak dipertanyakan lagi? Karena tindakan ‘tidak lagi mempertanyakan kebenaran’ ini tidak berlaku untuk semua orang. Orang lain malah bisa sangat tidak setuju atau sangat mempertanyakan ‘kebenaran yang tidak dipertanyakan’ itu tadi. Jadi, kebenaran di situ dianggap bersifat relatif. Oleh karena itulah lebih tepat jika kebenaran yang relatif itu disebut sebagai ‘asumsi’, anggapan, saja, bukan dalil atau hukum. b. Etos / Nilai-nilai (Ethos / Values) - (2) Setiap kegiatan ilmiah juga selalu didasarkan pada sejumlah kriteria atau patokan yang digunakan untuk menentukan apakah sesuatu itu baik atau buruk, benar atau sa-lah, bermanfaat atau tidak. Patokanpatokan inilah yang biasa disebut nilai atau etos. Dinyatakan atau tidak nilai-nilai selalu ada di balik setiap kegiatan ilmiah, karena di situ selalu ada persoalan benar atau salah, bermanfaat atau tidak. Dengan patokan inilah seorang ilmuwan akan menilai hasil penelitian ilmuwan yang lain, kinerja mereka atau produktivitas mereka. Dalam sebuah paradigma nilai-nilai ini paling tidak mengenai: (a) ilmu pengetahuan (b) ilmu sosial-budaya; (c) penelitian ilmiah; (d) analisis ilmiah; (e) hasil penelitian. Nilai-nilai ini selalu ada dalam setiap cabang ilmu, tetapi rumusan, penekanan dan keeksplisitannya berbedabeda. Ada cabang ilmu pengetahuan yang nilainya lebih menekankan Bab 2 35 pada manfaat ilmu, tetapi lebih bersifat implisit, sedang pada disiplin lain nilai ini dibuat sangat eksplisit. Nilai-nilai mana yang ditekankan oleh suatu komunitas atau organisasi ilmuwan bisa berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya masyarakat tempat para ilmuwan tersebut menjalankan aktivitas keilmuan me-reka. Meskipun nilai-nilai ini pada umumnya menyatakan tentang halhal yang baik, yang seharusnya, tetapi sebenarnya nilai-nilai juga berkenaan dengan yang tidak baik, yang buruk. Oleh karena itu, bisa pula nilai yang dibuat eksplisit bukanlah yang baik, tetapi yang buruk. Hal ini dilakukan mungkin dengan tujuan agar para ilmuwan dapat lebih terjaga dari melakukan hal-hal yang buruk. Nilai yang baik berkenaan dengan ilmu pengetahuan misalnya adalah nilai yang mengatakan, “ilmu pengetahuan yang baik adalah yang bermanfaat bagi kehidupan manusia”; atau “ilmu pengetahuan yang baik adalah yang teori-teorinya bisa bersifat universal”; atau “ilmu pengetahuan yang baik adalah yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur tertentu yang dapat mencegah masuknya unsur subyektivitas peneliti”, dan sebagainya. Nilai-nilai yang buruk misalnya adalah, “ilmu pengetahuan yang buruk adalah yang tidak memberikan manfaat kepada umat manusia”; atau “ilmu pengetahuan yang buruk adalah yang membuat manusia semakin jauh dari Sang Pencipta”. c. Model-model (Models) - (3) Model adalah perumpamaan, analogi, atau kiasan tentang gejala yang dipelajari. Seringkali model juga terlihat seperti asumsi dasar. Meskipun demikian, model bukan-lah asumsi dasar. Sebagai perumpamaan dari suatu kenyataan, sebuah model bersifat menyederhanakan (Inkeles, 1964). Artinya, tidak semua aspek, sifat, atau unsur dari realita dapat tampil dalam sebuah model. Model dapat dibedakan menjadi dua yakni: (1) model utama (primary model) dan model pembantu (secondary model). Model yang dimaksudkan di sini adalah primary model (Ahimsa-Putra, 2009). Model utama merupakan model yang lebih dekat dengan asumsi dasar. Model ini merupakan menjadi pembimbing seorang peneliti dalam 36 Paragima Profetik... mempelajari suatu gejala. Model ini bisa berupa kata-kata (uraian) maupun gambar, namun umumnya berupa uraian. Berbeda halnya dengan model pembantu yang selain umumnya berupa gambar, model ini juga biasa digunakan untuk memudahkan seorang ilmuwan menjelaskan hasil analisisnya atau teorinya. Model ini bisa berupa diagram, skema, bagan atau sebuah gambar, yang akan membuat orang lebih mudah mengerti apa yang dijelaskan oleh seseorang. Jadi kalau model utama harus sudah ada sebelum seorang peneliti melakukan penelitiannya, model pembantu biasanya muncul dalam hasil analisis atau setelah penelitian dan analisis dilakukan (Ahimsa-Putra, 2009). Sebagai perumpamaan dari suatu gejala atau realita tertentu sebuah model bersifat menyederhanakan gejala itu sendiri. Artinya, tidak semua aspek, sifat atau unsur dari gejala tersebut ditampilkan dalam model. Seorang peneliti yang mengawali penelitiannya dengan mengatakan bahwa kebudayaan itu seperti organisma atau mahluk hidup, pada dasarnya telah menggunakan model organisme dalam penelitiannya. Apakah kebudayaan itu organisme? Tentu saja bukan. Akan tetapi orang boleh saja mengumpa-makannya seperti organisme, karena memang ada kenyataan-kenyataan yang dapat mendukung pemodelan seperti itu. Jadi sebuah model muncul karena adanya persamaan-persamaan tertentu antara fenomena satu dengan fenomena yang lain. Perbedaan pada penekanan atas persamaan-persamaan inilah yang kemudian membuat ilmuwan yang satu menggunakan model yang berbeda dengan ilmuwan yang lain. Persamaan-persamaan ini pula yang kemudian membimbing seorang ilmuwan ke arah model tertentu, yang berarti ke arah penjelasan tertentu tentang gejala yang dipelajari. Pada saat yang sama, sebuah model berarti juga membelokkan si ilmuwan dari penjelasan yang lain. Oleh karena itu, sebuah model bisa dikatakan membimbing, tetapi bisa pula ‘menyesatkan’. Oleh kare-na itu pula tidak ada model yang salah atau paling benar. Semua model benar belaka. Yang membedakannya adalah produktivitasnya (Inkeles, 1964). Artinya, implikasi-implikasi teoritis dan metodologis apa yang bakal lahir dari Bab 2 37 penggunaan model tertentu dalam mempelajari suatu gejala. Sebuah model yang banyak menghasilkan implikasi teoretis dan metodologis merupakan sebuah model yang produktif. Meskipun demikian, seorang ilmuwan bisa saja memilih sebuah model yang tidak begitu produktif, karena dianggap dapat memberikan pemahaman baru atas gejala yang dipelajari. Biasanya produktivitas sebuah model tidak dapat ditentukan dari awal, karena dalam perkembangan selanjutnya ilmuwan-ilmuwan lain mungkin saja akan dapat merumuskan pertanyaan-pertanyaan baru yang tak terduga berdasarkan atas model tersebut (Ahimsa-Putra, 2009). d. Masalah yang Diteliti / yang Ingin Dijawab - (4) Ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab atau hipotesa yang ingin diuji kebenarannya. Setiap paradigma memiliki masalahmasalahnya sendiri, yang sangat erat kaitannya dengan asumsi-asumsi dasar dan nilai-nilai. Oleh karena itu, rumusan masalah dan hipotesa harus dipikirkan dengan seksama dalam setiap penelitian, karena di baliknya terdapat sejumlah asumsi dan di dalamnya terdapat konsepkonsep terpenting. Oleh Kuhn unsur ini disebut exemplar. Suatu penelitian selalu berawal dari suatu kebutuhan, keperluan, yaitu keperluan untuk (a) memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertentu, atau keinginan (b) membuktikan kebenaran empiris dugaan-dugaan atau pernyataan-pernyataan tertentu (Ahimsa-Putra, 2009). Penelitian untuk memenuhi kebutuhan pertama selalu berawal dari sejumlah pertanyaan (questions) mengenai gejala-gejala tertentu yang dianggap menarik, aneh, asing, menggelisahkan, menakutkan, merugikan, dan seterusnya, sedang penelitian kedua selalu berawal dari sejumlah pernyataan yang masih perlu dan ingin dibuktikan kebenarannya (hypothesis) atau hipotesa. Oleh karena itu dalam setiap penelitian harus ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab, dan/atau hipotesahipotesa yang ingin dibuktikan. Penelitian yang berawal dari beberapa pertanyaan tidak perlu lagi menggunakan hipotesa, demikian pula penelitian yang berawal dari sejumlah hipotesa, tidak perlu lagi 38 Paragima Profetik... menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Meskipun demikian, kalau suatu penelitian dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan sekaligus menjawab hipo-tesa hal itu juga tidak dilarang (Ahimsa-Putra, 2009). e. Konsep-konsep Pokok (Main Concepts, Key Words) - (5) Dalam ilmu sosial-budaya, konsep dimaknai berbeda-beda. Di sini, secara sederhana konsep didefinisikan sebagai istilah-istilah atau kata-kata yang diberi makna tertentu sehingga membuatnya dapat digunakan untuk menganalisis, memahami, menafsirkan dan menjelaskan peristiwa atau gejala sosial-budaya yang dipelajari (Ahimsa-Putra, 2009) Apa contoh dari konsep ini? Banyak sekali dalam ilmu sosialbudaya. Misalnya: masyarakat, kebudayaan, pendidikan, sekolah, konflik, sukubangsa, kepribadian, kerjasama, dan sebagainya. Kamus antropologi, kamus sosiologi, dan sejenisnya, merupakan kumpulan penjelasan konsep-konsep yang dipandang penting dalam kajian antropologi dan sosiologi. Banyak istilah-istilah di situ merupakan istilah yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian belum tentu kita mengetahui makna istilah-istilah tersebut dengan baik, bahkan tidak sedikit yang salah dalam menggunakannya, terutama jika istilah tersebut berasal dari bahasa asing. Ketika sebuah istilah diberi makna tertentu oleh seorang ilmuwan yang kebetulan membutuhkan istilah tersebut untuk menjelaskan sebuah gejala, pada saat itulah istilah tersebut -berdasarkan definisi di atasmenjadi ‘konsep’. Sebagai contoh adalah kata ‘kebudayaan’. Pada mulanya istilah kebudayaan adalah istilah sehari-hari, yang kemudian diberi definisi oleh orang-orang tertentu, di antaranya adalah Ki Hadjar Dewantoro. Kemudian beberapa orang lain memberikan definisi baru, di antaranya adalah Koentjaraningrat. Semenjak itu, kata ‘kebudayaan’ menjadi sebuah konsep yang penting dalam dunia ilmu pengetahuan, terutama ilmu sosialbudaya, khususnya lagi dalam antropologi (Ahimsa-Putra, 2009). Sebuah konsep dalam ilmu sosial-budaya bisa diberi definisi atau batasan berbagai macam. Dalam hal ini perlu diingat bahwa tidak ada Bab 2 39 definisi yang paling benar, karena setiap konsep dapat diberi definisi dari sudut pandang tertentu, dengan cara tertentu. Yang perlu diperhatikan adalah apakah definisi sebuah konsep memungkinkan peneliti mempelajari, memahami dan menjelaskan gejala yang diteliti dengan baik. Oleh karena itu, sebelum merumuskan sebuah definisi seyogyanya peneliti melakukan kajian pustaka yang cukup komprehensif agar dapat memperoleh berbagai definisi yang telah dibuat oleh para ilmuwan lain berkenaan dengan konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitiannya (Ahimsa-Putra, 2009). f. Metode-metode Penelitian Research) - (6) ( Methods of Berkenaan dengan metode penelitian ini umumnya kita mengenal pembedaan antara ‘metode penelitian kuantitatif’ dan ‘metode penelitian kualitatif’. Meskipun demikian banyak sekali mahasiswa dan sarjana ilmu sosial-budaya yang mempunyai pengertian kurang lengkap tentang ‘metode penelitian’ ini, sehingga ketika mereka ditanya “di mana letak kualitatifnya dan kuantitatifnya sebuah metode?”, mereka tidak dapat menjawab. Selain itu, banyak juga ilmuwan sosial-budaya yang hanya mengetahui satu jenis metode saja, yaitu yang kuantitatif, sehingga semua masalah selalu diteliti dengan menggunakan metode yang sama, padahal sebenarnya tidak demikian. Lebih jelek lagi, karena tidak mengetahui jenis metode penelitian yang lain, metode penelitian itulah (yang kuantitatif) yang kemudian dianggap sebagai satu-satunya metode penelitian yang ilmiah (Ahimsa-Putra, 2009). Dalam pembicaraan di sini ‘penelitian’ harus diartikan sebagai ‘pengumpulan data’. Oleh karena itu, metode penelitian kualitatif dan kuantitatif tidak lain adalah metode atau cara guna memperoleh, mengumpulkan, data kualitatif dan data kuantitatif. Jadi yang bersifat ‘kuantitatif’ atau ‘kualitatif’ bukanlah metodenya, tetapi datanya. Selanjutnya, sifat data ini juga sangat menentukan cara kita untuk mendapatkannya. Untuk itu kita perlu tahu ciri-ciri penting yang ada pada masing-masing data. Dilihat dari sudut pandang ini, maka sebenarnya tidak ada 40 Paragima Profetik... pemisahan dan tidak perlu ada pemisahan yang sangat tegas dan kaku antara “penelitian kualitatif” dan ‘penelitian kuantitatif”, sebagaimana sering dikatakan oleh sebagian ilmuwan sosial-budaya yang kurang memahami tentang metode-metode penelitian. Yang penting dalam suatu penelitian adalah bagaimana dapat menjawab pertanyaanpertanyaan yang dikemukakan dengan memuaskan, dengan meyakinkan, dan ini sangat tergantung pada data yang dikemukakan. Data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian bisa berupa data kualitatif, data kuantitatif, atau kedua-duanya, dan sebuah penelitian bisa saja memerlukan dan memanfaatkan dua jenis data ini untuk menjawab masalah-masalahnya. Data kuantitatif dikumpulkan dengan cara yang berbeda dengan data kualitatif. Oleh karena ciri dan sifatnya yang berbeda ini, maka analisis terhadap data ini juga berbeda (Ahimsa-Putra, 2009). Data kuantitatif adalah kumpulan simbol -bisa berupa pernyataan, huruf atau angka- yang menunjukkan suatu jumlah (quantity) atau besaran dari suatu gejala, seperti misalnya jumlah penduduk, jumlah laki dan perempuan, jumlah anak sekolah, jumlah rumah, jumlah tempat ibadah, luas sebuah kelurahan, jumlah padi yang dipanen, dalamnya sebuah sumur, dan sebagainya. Data kuantitatif dapat diperoleh dari kantor statistik atau kantor pemerintah (kabupaten, kecamatan, kelurahan, dst.) atau dari penghitungan butir-butir tertentu yang ada dalam kuesioner (daftar pertanyaan) yang diedarkan dalam suatu penelitian, atau dari pernyataan informan (Ahimsa-Putra, 2009). Data kualitatif tidak berupa angka tetapi berupa pernyataanpernyataan mengenai isi, sifat, ciri, keadaan, dari sesuatu atau gejala, atau pernyataan mengenai hubungan-hubungan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sesuatu ini bisa berupa benda-benda fisik, pola-pola perilaku, atau gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, bisa pula peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu masyarakat (Ahimsa-Putra, 2009). Dari berbagai penelitian sosial-budaya yang telah dilakukan, saya menemukan bahwa data kualitatif ini biasanya mengenai antara lain: Bab 2 41 (1) nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan; (2) kategori-kategori sosial dan budaya; (3) ceritera (4) percakapan; (5) pola-pola perilaku dan interaksi sosial; (6) organisasi sosial; (7) lingkungan fisik (Ahimsa-Putra, 2009). Skema 1. Data Kuantitatif dan Kualitatif luas (wilayah, kampung, sawah, dsb. Kuantitatif jumlah (penduduk, bangunan, koperasi, dsb.) berat (hasil panen, badan, dsb.) Data nilai, pandangan hidup, norma, aturan kategori sosial-budaya Kualitatif ceritera percakapan pola perilaku dan interaksi sosial organisasi sosial lingkungan fisik (Sumber: Ahimsa-Putra, 2009) Metode adalah cara, sedang penelitian adalah kegiatan mengumpulkan data. Jadi metode penelitian adalah cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, sedang “metodologi penelitian” adalah ilmu tentang cara-cara mengumpulkan data, termasuk di dalamnya jenisjenis data. Ada berbagai cara untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian, dan cara mana yang akan digunakan tergantung pada jenis data yang diperlukan. Cara dan kegiatan untuk mengumpulkan data kualitatif tidak akan bisa sama dengan kegiatan mengumpulkan data kuantitatif. Atas dasar jenis data yang di-perlukan inilah muncul kemudian berbagai metode pengumpulan data (Ahimsa-Putra, 2009). Berdasarkan atas jenis datanya metode penelitian ilmu sosial-budaya dengan sendirinya hanya dapat dibedakan menjadi (a) metode penelitian kuantitatif atau metode pengumpulan data kuantitatif, dan (b) metode penelitian kualitatif atau metode pengumpulan data kualitatif. Dalam masing-masing metode penelitian ini terdapat sejumlah metode penelitian lagi, yang penggunaannya biasanya didasarkan atas pertimbanganpertimbangan praktis, yakni ketersediaan waktu, biaya dan tenaga. 42 Paragima Profetik... Dalam metode pengumpulan data kuantitatif, yang selanjutnya kita sebut metode penelitian kuantitatif, terdapat misalnya (a) metode kajian pustaka; (b) metode survei dan (c) metode angket. Dalam metode penelitian kualitatif terdapat (a) metode kajian pustaka; (b) metode pengamatan; (c) metode pengamatan berpartisipasi (participant observation); (d) metode wawancara sambil lalu; (e) metode wawancara mendalam, dan (f) metode mendengarkan (Ahimsa-Putra, 2009). g. M e t o d e - m e t o d e A n a l i s i s Analysis) - (7) (Methods of Metode analisis data pada dasarnya adalah cara-cara untuk memilahmilah, menge-lompokkan data -kualitatif maupun kuantitatif- agar kemudian dapat ditetapkan relasi-relasi tertentu antara kategori data yang satu dengan data yang lain. Sebagaimana halnya metode penelitian, metode analisis kualitatif dan metode analisis kuantitatif harus diartikan sebagai metode menganalisis data kualitatif dan metode menganalisis data kuantitatif. Mengelompokkan data kuantitatif memerlukan siasat atau cara yang berbeda dengan mengelompokkan data kualitatif, karena sifat dan ciri data tersebut memang berbeda (Ahimsa-Putra, 2009). Metode analisis data kualitatif pada dasarnya sangat memerlukan kemampuan untuk menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan di antara data kualitatif, dan ini hanya dapat dilakukan apabila konsepkonsep teoritis yang digunakan didefinisikan dengan baik. Persamaan dan perbedaan ini tidak begitu mudah ditemukan, namun bilamana pada saat pengumpulannya data ini sudah dikelompokkan terlebih dahulu hal itu akan mempermudah analisis lebih lanjut. Berkenaan dengan metode analisis ini yang paling perlu diperhatikan adalah tujuan akhir dari suatu kerja analisis. Dengan memperhatikan secara seksama pertanyaan penelitian yang kita kemukakan sebenarnya kita sudah dapat menentukan sejak awal metode analisis seperti apa yang akan lakukan atau kita perlukan. Meskipun ada berbagai macam jenis metode analisis, namun secara umum kita dapat mengatakan bahwa tujuan akhir analisis adalah menetapkan hubungan-hubungan antara suatu Bab 2 43 variable/gejala /unsur tertentu dengan variable/gejala/unsur yang lain, dan menetapkan jenis hubungan yang ada di situ. Setiap paradigma selalu mempunyai metode analisis tertentu, karena metode analisis inilah yang kemudian akan menentukan corak hasil analisis atau teorinya, sehingga teori yang muncul dalam sebuah paradigma tidak akan sama dengan teori yang muncul dalam paradigma yang lain (Ahimsa-Putra, 2009). h. H a s i l A n a l i s i s / T e o r i Analysis / Theory) - (8) (Results of Apabila kita dapat melakukan analisis atas data yang tersedia dengan baik dan tepat, maka tentu akan ada hasil dari analisis tersebut, yang dapat dikatakan sebagai “kesimpulan” kita. Hasil analisis ini harus menyatakan relasi-relasi antarvariabel, antar-unsur atau antargejala yang kita teliti. Jika hasil analisis kita tidak berhasil mencapai ini maka hal itu bisa berarti tiga hal. Pertama, data yang kita analisis mengandung beberapa kesalahan mendasar. Kedua, analisis kita salah arah. Ketiga, analisis kita masih kurang mendalam, dan ini mungkin juga disebabkan oleh kurangnya data yang kita miliki (Ahimsa-Putra, 2009). Setelah kita menganalisis berbagai data yang telah kita peroleh dengan menggunakan metode-metode tertentu kita akan memperoleh suatu kesimpulan tertentu, suatu pendapat tertentu berkenaan dengan gejala yang dipelajari. Pendapat ini bisa berupa pernyataan-pernyataan yang menunjukkan relasi antara suatu variabel dengan variabel yang lain, atau pernyataan yang menunjukkan “hakikat” (the nature) atau ciri dan keadaan dari gejala yang kita teliti. Hasil analisis yang berupa pernyataan-pernyataan tentang hakikat gejala yang diteliti atau hubungan antarvariabel atau antargejala yang diteliti inilah yang kemudian biasa disebut sebagai teori. Dengan kata lain, teori adalah pernyataan mengenai hakekat sesuatu (gejala yang diteliti) atau mengenai hubungan antar variabel atau antar gejala yang diteliti, yang sudah terbukti kebenarannya (Ahimsa-Putra, 2009) Kalau cakupan (scope) penelitian kita luas, data yang kita analisis berasal dari banyak masyarakat dan kebudayaan, dan teori yang kita 44 Paragima Profetik... kemukakan dapat memberikan penjelasan yang berlaku umum, “universal”, melampaui batas-batas ruang dan waktu, maka biasanya dia akan disebut sebagai teori besar (grand theory). Kalau teori tersebut hanya kita tujukan untuk menjelaskan gejala-gejala tertentu yang agak umum, namun tidak cukup universal, maka dia lebih tepat disebut sebagai teori menengah (mid-dle-range theory) (Merton, 19 ). Bilamana teori yang kita sodorkan hanya berlaku untuk gejala-gejala yang kita teliti saja, yang terjadi hanya dalam masyarakat dan kebudaya-an yang kita teliti, maka dia lebih tepat disebut teori kecil (small theory). Di sini pernyataan tentang hubungan antar variabel tersebut lebih kecil atau lebih terbatas cakupannya (Ahimsa-Putra, 2009). i. Representasi (Etnografi) - (9) Representasi atau penyajian adalah karya ilmiah yang memaparkan kerangka pemikiran, analisis dan hasil analisis yang telah dilakukan, yang kemudian menghasilkan kesimpulan atau teori tertentu. Representasi ini bisa berupa skripsi (pada S-1), tesis (pada S-2), disertasi (pada S-3), laporan penelitian, makalah, artikel ilmiah (dalam jurnal ilmiah), atau sebuah buku. Dalam antropologi, representasi ini biasa disebut etnografi. Dalam sejarah disebut historiografi. Dalam arkeologi ada yang menyebutnya sebagai paleoetnografi (Ahimsa-Putra, 2009). Representasi atau etnografi merupakan tulisan yang dihasilkan oleh seorang peneliti setelah dia melakukan penelitian atas satu atau beberapa masalah dengan menggunakan paradigma tertentu. Oleh karena itu sebuah paradigma belum akan terlihat sebagai sebuah paradigma sebelum ada etnografinya. Sebuah paradigma yang tidak memiliki etnografi dengan corak tertentu belum dapat dikatakan sebagai paradigma yang utuh. 3. Skema Paradigma Urutan atau jenjang unsur-unsur paradigma di atas dapat digambarkan dengan skema seperti berikut ini. Bab 2 45 Skema 2. Unsur-unsur Paradigma dalam Ilmu Sosial-Budaya representasi hasil analisis (teori) metode analisis metode penelitian konsep-konsep selalu eksplisit masalah yang ingin diteliti model tidak selalu eksplisit asumsi dasar nilai-nilai (Sumber: Ahimsa-Putra, 2008) Skema itu disusun dengan anggapan bahwa dalam sebuah paradigma unsur ‘asumsi dasar’ merupakan dasar dari unsur-unsur yang lain, dan sudah ada sebelum adanya unsur-unsur yang lain. Oleh karena itu, asumsi-asumsi dasar ditempatkan paling bawah. Representasi merupakan unsur yang terakhir muncul dalam sebuah paradigma, sehingga unsur ini ditempatkan di atas. Asumsi-asumsi dasar dapat dikatakan sebagai unsur-unsur paradigma yang paling dasar, paling tersembunyi, paling implisit dan karena itu biasanya juga paling tidak disadari. Oleh karena itu berada ditempatkan di paling bawah. Demikian juga halnya nilai-nilai. Walaupun, nilai-nilai ini biasanya lebih disadari daripada asumsi dasar. Seorang ilmuwan yang baik akan selalu tahu dan sadar tentang nilainilai keilmuan yang harus diikuti dalam setiap kegiatan ilmiah. Ilmuwan atau peneliti umumnya cukup me-ngetahui nilai-nilai universal yang ada dalam kegiatan ilmiah. Model-model merupakan unsur paradigma yang sudah lebih jelas atau lebih kong-krit dibandingkan dengan asumsi-asumsi dasar, 46 Paragima Profetik... walaupun tingkat keabstrakan dan keimplisitannya seringkali sama dengan asumsi dasar, namun unsur model ini juga lebih sederhana dibandingkan dengan elemen asumsi dasar. Sebuah model umumnya merupakan impilkasi lebih lanjut dari asumsi dasar yang dianut. Oleh karena itu, model ditempatkan setelah asumsi dasar. Masalah-masalah ingin diteliti, yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan atau hipotesa, merupakan unsur yang harus eksplisit, sehingga unsur ini ditempatkan di atas garis pemisah antara unsur-unsur yang (bisa) implisit dengan unsur-unsur yang harus eksplisit. Masalah-masalah penelitian juga merupakan implikasi dari asumsi dan model yang dianut, walaupun hal ini tidak selamanya disadari oleh para peneliti. Konsep-konsep pokok juga merupakan unsur paradigma yang kongkrit, yang eksplisit karena dalam setiap penelitian makna konsepkonsep ini sudah harus dipaparkan dengan jelas. Seperti halnya masalah penelitian, konsep-konsep ini sudah bersifat eksplisit dan disadari, diketahui, walaupun tidak selalu dimengerti dengan baik segala implikasi metodologisnya oleh para peneliti. Metode penelitian dan metode analisis merupakan tahap-tahap pewujudan dari asumsi-asumsi dasar, model dan konsep dalam sebuah kegiatan penelitian. Pelaksa-naan atau penerapan metode-metode ini didasarkan pada apa-apa yang ada dalam asumsi dasar, model dan konsep. Dengan kata lain metode-metode ini merupakan tahap pelaksanaan penelitian yang dibimbing oleh unsur-unsur paradigma yang sudah ada sebelumnya. Penelitian dengan menggunakan konsepkonsep tertentu akan me-merlukan metode yang berbeda dengan penelitian yang menggunakan konsep-konsep yang lain. Hasil analisis merupakan unsur yang muncul setelah dilakukannya analisis atas data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Hasil analisis ini juga harus dinyatakan secara eksplisit, tegas dan jelas. Jika tidak tegas dan jelas maka penelitian yang telah dilakukan akan dinilai kurang berhasil, dan ini akan membuat telaah atas paradigma yang telah digunakan semakin dipertajam. Bab 2 47 Representasi merupakan elemen terakhir dari sebuah paradigma, dan di sinilah sebuah paradigma akan dinilai keberhasilannya untuk menjawab persoalan-persoalan tertentu. Sebagai hasil akhir, representasi ini sedikit banyak akan mencerminkan keseluruhan elemen-elemen yang ada dalam sebuah paradigma. Oleh karena itu, dalam skema di atas, semua ujung panah akhirnya mengarah pada unsur representasi ini. Skema di atas akan menjadi terbalik, yakni unsur representasi berada di bawah, jika dikatakan bahwa unsur-unsur paradigma diturunkan dari asumsi-asumsi dasar. Skema yang terbalik ini disusun atas dasar tingkat keabstrakan dan keimplisitan dari unsur-un-sur paradigma. Semakin abstrak, implisit dan tidak disadari sebuah unsur, akan semakin tinggi tempatnya dalam skema di atas. Meskipun demikian, semuanya akan berakhir pada representasi atau etnografi. C. Paradigma Profetik dan Islam Dalam kaitannya dengan ilmu (sosial) profetik mas Kunto antara lain mengatakan bahwa basis dari ilmu tersebut adalah Islam. Pertanyaannya adalah: apa yang dimaksud dengan Islam di sini? Oleh karena Islam dapat dimaknai berbagai macam, maka perlu ada rumusan minimal tentang apa yang dimaksud dengan Islam di sini. Untuk sementara, Islam di sini dimaknai sebagai keseluruhan perangkat simbol yang berbasis pada simbol-simbol yang bersumber pada kitab Al Qur’an dan sunnah Nabi Muhammad s.a.w. sebagai utusan Allah s.w.t. yang menjelaskan dan mewujudkan berbagai hal -jika bukan semua hal yang ada- dalam Al Qur’an. 1. Basis Epistemologis Menurut kerangka paradigma di atas, basis epistemologis di sini tidak lain adalah komponen-komponen yang ada di bawah garis pemisah antara yang eksplisit dengan yang tidak eksplisit, yaitu komponen (1) asumsi dasar; (2) etos, nilai-nilai, dan (3) model. Jadi, unsur-unsur yang umumnya bersifat implisit. Komponen asumsi dasar dari sebuah Paragima Profetik... 48 paradigma biasanya terdiri dari sejumlah asumsi dasar. Begitu pula komponen nilai-nilai. Komponen model biasanya hanya satu, tetapi hal ini tergantung pemaknaan kita terhadap model itu sendiri, karena seringkali model sangat mirip bahkan sama dengan asumsi dasar. a. Basis Utama: Al Qur’an dan Sunnah Rasul Al Qur’an dan Sunnah Rasulullah dalam konteks ilmu (sosialbudaya) profetik me-rupakan basis utama dari keseluruhan basis ilmu tersebut. Oleh karena itu segala se-suatu yang ada dalam Al Quran dan sunnah Rasulullah harus diketahui dan dipahami dengan baik terlebih dulu, untuk dapat dijadikan landasan bagi keseluruhan bangunan ilmu pengetahuan (sosial-budaya) yang profetik. Tentu saja tidak semua unsur dalam Al Quran dan sunnah Rasulullah relevan dengan pengembangan ilmu pengetahuan (sosialbudaya) profetik. Untuk itu, pengetahuan dan pemahaman tentang unsur-unsur yang relevan akan sangat membantu pengembangan ilmu pengetahuan tersebut. Di sini diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang baik dan benar mengenai Al Quran dan sunnah Rasulullah serta pengetahuan dan pemahaman mengenai filsafat ilmu pengetahuan yang biasa. Al Qur’an dan sunnah Rasulullah s.a.w. dapat dikatakan sebagai sebuah sistem ajaran -yang disebut “agama Islam”- yang ditujukan untuk membangun sebuah kehi-dupan yang berlandaskan pada dua hal penting, yakni rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman merupakan basis keyakinan, basis kepercayaan, basis yang terdiri dari dua macam: basis kognisi (pikiran) dan basis afeksi (perasaan). b. Rukun Iman Rukun iman adalah hal-hal yang harus diyakini oleh seorang Muslim, yang terdiri dari enam hal, yaitu iman: (1) kepada Allah, (2) kepada malaikat, (3) kepada Kitab-kitab, (4) kepada Rasul-rasul (para Nabi), (5) kepada Hari Kiamat, Hari Pengadilan dan (6) kepada Takdir (Qadha dan Qadar). Rukun iman ini berada pada bidang keyakinan tentang Bab 2 49 pandangan-pandangan tertentu dalam agama. Agar relevan dengan ilmu (sosial) profetik, maka Rukun Iman ini perlu ditransformasikan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan konteksnya, yakni konteks keilmuan. Bagaimana mentransformasikan enam iman tersebut? Jika direnungkan lebih lanjut, “iman” tersebut tidak lain adalah “relasi”. Beriman kepada Allah berarti “membangun relasi dengan Allah”, dan relasi yang paling tepat adalah “pengabdian”, “kepadaMulah aku mengabdi”. Dalam konteks ilmu profetik, Allah di sini ditransformasikan menjadi Pengetahuan, karena Allah adalah Sumber Pengetahuan. Beriman kepada Allah dalam konteks ilmu profetik adalah mengimani pengetahuan itu sendiri. Beriman kepada malaikat berarti “membangun relasi dengan malaikat”, dan relasi yang tepat adalah “persahabatan”, karena malaikat adalah sahabat atau teman orang yang beriman. Beriman kepada Kitab adalah membangun relasi dengan kitab, dan relasi yang tepat adalah “pembacaan”, karena kitab adalah sesuatu yang dibaca. Beriman kepada Nabi adalah membangun relasi dengan Nabi, dan relasi yang tepat adalah “perguruan dan persahabatan”. Artinya, seorang Muslim memandang Nabi sebagai guru yang memberikan pengetahuan, sekaligus juga sahabat, sebagaimana hubungan yang terjadi antara Nabi Muhammad s.a.w. dengan para sahabatnya. Beriman kepada Hari Kiamat adalah membangun relasi dengan hari Kiamat, dan relasi yang tepat adalah “pencegahannya”, karena Kiamat dalam konteks ini dapat ditafsirkan sebagai “kehancuran”. Beriman kepada Takdir adalah membangun relasi dengan Takdir, dan relasi yang tepat adalah “penerimaannya”. Artinya seorang muslim memandang takdir sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindarkan, dan karena itu relasi yang tepat adalah menerimanya. Takdir dalam konteks keilmuan dapat ditafsirkan sebagai “hukum alam”. Dalam konteks ilmu (sosial) profetik maka transformasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut ini. Paragima Profetik... 50 Manusia Ilmuwan pengabdian pengabdian Manusia Ilmuwan persahabatan persahabatan Malaikat Kolega Manusia Ilmuwan pembacaan pembacaan Kitab Kitab Ilmiah Manusia Ilmuwan perguruan + persahabatan perguruan + persahabatan Allah s.w.t. Ilmu pengetahuan Nabi Tokoh Manusia Ilmuwan penundaan penundaan Hari Kiamat Akhir Manusia Ilmuwan penerimaan penerimaan Takdir Ilmu Terbatas c. Rukun Islam Sebagaimana Rukun Iman, dalam konteks ilmu (sosial) profetik rukun Islam tentunya perlu ditransformasikan, dan yang ditransformasikan di sini bukan hanya keyakinan tetapi juga rituil adalah keyakinan, prinsip diikuti, dianut, dan hal-hal yang harus dijalankan oleh setiap orang Islam. Rukun Islam ada lima: (a) membaca kalimat syahadat; (b) mendirikan sholat; (c) menjalankan puasa; (d) mengeluarkan zakat; dan (e) naik haji. Rukun Islam ini perlu ditransformasikan ke dalam praktik kehidupan ilmiah sehari-hari, sebagaimana halnya rukun Islam juga harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sinilah rukun Islam akan menjadi wujud dari etos yang ada dalam ilmu (sosial) profetik, dan basis dari praktik kehidupan ilmiah ini adalah transformasi rukun iman yang pertama, yaitu pengabdian, karena pada dasarnya rukun Islam adalah perwujudan dalam bentuk tindakan atau praktik, dari keimanan. Dari telaah saya atas berbagai paradigma dalam ilmu sosial-budaya saya menemukan bahwa unsur asumsi dasar terdiri dari beberapa asumsi dasar lagi. Asumsi-asumsi dasar ini antara lain adalah mengenai: (a) basis pengetahuan; (b) objek material; (c) gejala yang diteliti; (d) ilmu pengetahuan; (e) ilmu sosial-budaya/alam; (f) disiplin. Berkenaan Bab 2 51 dengan ilmu (sosial-budaya) profetik, isi dari asumsi-asumsi dasar ini sebagian sama dengan ilmu-ilmu di Barat pada umumnya, sebagian yang lain berbeda. Skema 3. Basis Epistemologis Ilmu Profetik Asumsi dasar tentang Gejala Yang Diteliti indera kemampuan strukturasi dan simbolisasi bahasa wahyu - ilham sunnah Rasulullah saw. asal - mula sebab - sebab hakekat asal - mula sebab - sebab hakekat Asumsi dasar tentang Ilmu Pengetahuan tujuan hakekat macam Asumsi dasar tentang Basis Pengetahuan Rukun Iman Basis Epistemologis Al Quran dan Sunnah Rasul Rukun Islam Asumsi dasar tentang Obyek Material Asumsi dasar tentang Ilmu Sosial/Budaya Alam/Profetik Asumsi dasar tentang Disiplin Profetik tujuan hakekat macam tujuan hakekat macam 2. Asumsi Dasar tentang Basis Pengetahuan Ilmu profetik memiliki asumsi-asumsi dasar tentang basis dari pengetahuan manusia. Asumsi-asumsi ini ada yang sama dengan asumsiasumsi yang ada dalam ilmu pengetahuan empiris lainnya, ada pula yang tidak, sebab kalau basis pengetahuan ini semuanya sama, maka tidak akan ada bedanya antara ilmu profetik dengan ilmu-ilmu empiris lainnya. Berikut adalah basis yang memungkinkan manusia memiliki pengetahuan, dan dengan pengetahuan tersebut manusia dapat melakukan transformasi-transformasi dalam kehidupannya. a. Indera Sulit diingkari bahwa basis pengetahuan manusia adalah indera (sense), karena segala sesuatu yang ada di sekeliling manusia baru dapat diketahui adanya lewat inde-ra ini. Menurut Aristotle pengetahuan 52 Paragima Profetik... manusia berasal dari panca indera (lima indera): penglihatan (vision), pendengaran (hearing), perabaan (touch), pengecapan (taste) dan penciuman (smell), sementara Lucretius membagi indera menjadi empat, karena me-nurutnya penglihatan (vision) adalah semacam perabaan (touch) (Ratoosh, 1973). Pe-mikir-pemikir yang lain memiliki pendapat yang berbeda lagi. Pandangan-pandangan mereka ini tampaknya tidak lagi memadai untuk menampung berbagai pengalaman baru manusia, yang memberikan pengetahuan-pengetahuan baru. Pandangan yang modern mengenai indera kini tidak lagi didasarkan pada pandangan dari Aristotle, tetapi pada perbedaan-perbedaan anatomi, sehingga muncul klasifikasi indera yakni (a) indera khusus (special senses); (b) indera kulit (skin senses); (c) indera dalam (deep senses) dan (d) indera jeroan (visceral senses) (Ratoosh, 1973). Termasuk dalam indera khusus adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan dan vestibular sense. Indera kulit mencakup antara lain perabaan, pedih di kulit, dan indera suhu (temperature sense). Indera dalam meliputi antara lain otot, rasa di pergelangan, pedih di dalam. Indera jeroan (visceral) menyampaikan informasi mengenai apa yang terjadi pada organ tubuh di dalam. Mules, mual misalnya termasuk di sini. Dengan klasifikasi ini kita dapat memasukkan berbagai pengetahuan yang berasal tidak hanya dari pengalaman kita dengan apa yang ada di luar diri kita, tetapi juga yang berasal dari pengalamanpengalaman atas apa yang terjadi dalam tubuh kita sendiri. Berkenaan dengan ilmu (sosial-budaya) profetik, saya belum dapat mengatakan apakah pandangan modern mengenai indera tersebut akan dapat mencakup pengetahuan yang muncul dari kontak dengan dunia yang ghaib, yang tidak empiris, atau pengetahuan yang muncul lewat “wahyu”. Namun, untuk sementara persoalan itu kita kesampingkan sebentar agar diskusi mengenai basis yang lain bisa berjalan. Bab 2 b. Kemampuan (Akal) Strukturasi 53 dan Simbolisasi Pembicaraan mengenai basis pengetahuan manusia biasanya selalu menyebutkan “akal” atau “akal budi”. Manusia dapat memiliki pengetahuan karena dikaruniai akal. Akan tetapi konsep “akal” itu sendiri menurut hemat saya tidak begitu jelas maknanya. Akal biasanya juga disamakan dengan pikiran. Apa kira-kira wujud akal dan pikiran ini? Tidak begitu jelas. Oleh karena itu, konsep tersebut perlu dijelaskan lagi. Akal atau pikiran, menurut pandangan saya, tidak lain adalah kemampuan tertentu yang terdapat dalam otak manusia. Kemampuan ini bersifat genetis, sehingga dapat diwariskan secara biologis dari generasi ke generasi. Setiap manusia yang sehat atau normal memiliki kemampuan ini. Kemampuan apa ini? Pertama adalah kemampuan strukturasi (structuration), atau kemampuan untuk menstruktur, membuat atau membangun suatu struktur atau susunan atas berbagai rangsangan yang berasal dari pengalaman-pengalaman inderawi. Kedua adalah kemampuan simbolisasi (simbolization) atau kemampuan untuk membangun suatu hubungan, suatu relasi, antara sesuatu de-ngan sesuatu yang lain, sehingga terbangun relasi simbolik antara sesuatu dengan sesuatu tersebut yang membuat sesuatu bisa menjadi pelambang (simbol) dan yang lain adalah linambangnya (makna). Dengan kemampuan strukturasinya manusia dapat menyusun berbagai unsur pengalaman dan pengetahuan menjadi suatu bangunan dengan struktur tertentu, yang biasanya kita sebut sebagai sistem klasifikasi, sistem kategorisasi. Dengan kemampuan simbolisasinya manusia kemudian dapat memiliki perangkat komunikasi yang sangat efisien dan menjadi basis utama terbangunnya sistem pengetahuan dalam kehidupan manusia, yakni bahasa. c. Bahasa (Pengetahuan Kolektif) Bahasa sebagai basis pengetahuan manusia sangat jarang dibahas. Mungkin karena bahasa dipandang sebagai sesuatu yang berada di luar 54 Paragima Profetik... diri manusia. Kealpaan untuk menempatkan bahasa sebagai salah satu basis pengetahuan manusia menurut saya telah membuat kita alpa memperhatikan berbagai fenomena sosial-budaya yang kehadirannya berbasis pada bahasa, seperti misalnya wacana, dialog. Menurut hemat saya bahasa merupakan salah satu basis pengetahuan manusia yang sangat penting, setelah basis “akal” di atas. Kemampuan strukturasi dan simbolisasi yang terdapat dalam diri manusia merupakan basis kemampuan manusia untuk dapat berbahasa. Dalam kehidupan manusia, pengetahuan tidak hanya berasal dari pengalaman individu saja, tetapi juga berasal dari interaksi dan komunikasinya dengan individu-individu lain, dan komunikasi ini berlangsung melalui bahasa. Bahasa merupakan perangkat yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan apa-apa yang dirasakan, dialami, kepada manusia yang lain. Bahasa merupakan sebuah khasanah pengetahuan kolektif, pengetahuan sosial, yang menjadi sumber dan basis bagi pengetahuan individual. Pengetahuan individual yang kita miliki sebagian besar merupakan pengetahuan kolektif, karena kita mengetahui berbagai hal pertamatama melalui komunikasi dengan orang-orang lain di sekitar kita. Banyak pengetahuan tentang berbagai hal dalam kehidupan kita tidak berasal dari pengalaman kita secara langsung dengan hal-hal tersebut. Kita mengetahui mengenai ular yang berbahaya bukan dari pengalaman langsung digigit ular dan merasakan sakitnya, tetapi dari ceritera orang lain. Ilmu pengetahuan yang kita miliki sekarang merupakan hasil dari akumulasi pengalaman dan pengetahuan individu-individu lain di masa yang lampau. Ilmu pengetahuan tersebut tersimpan dalam bahasa. Oleh karena itu, bahasa dapat kita anggap sebagai salah satu basis dari pengetahuan. Bahasa sebagai unsur pembentuk pengetahuan manusia juga sangat penting dalam hubungannya dengan basis yang lain dari pengetahuan ilmu (sosial-budaya) profetik, yaitu wahyu. Wahyu yang dalam Islam diyakini sebagai petunjuk, pengetahuan yang berasal dari Dzat Tertinggi, Bab 2 55 sampai kepada manusia melalui sarana bahasa, dalam bentuk sepotong atau sejumlah ayat atau kalimat yang berisi pesan-pesan tertentu. d. Wahyu - Ilham Wahyu dalam pandangan mas Kunto -yang mengikuti pandangan Garaudy- merupa-kan komponen yang sangat menentukan dalam epistemologi ilmu (sosial-budaya) profetik. Pengakuan terhadap wahyu sebagai salah satu sumber pengetahuan yang bisa lebih tinggi otoritasnya daripada pengetahuan inderawi manusia merupakan unsur penting yang membedakan ilmu (sosial-budaya) profetik dengan ilmu (sosialbudaya) yang biasa. Dalam hal ini kita dapat mengikuti pandangan mas Kunto mengenai kedudukan pengetahuan yang berasal dari wahyu dalam epistemologi Islam. “Menurut epistemologi Islam, unsur petunjuk transendental yang berupa wahyu juga menjadi sumber pengetahuan yang penting. “Wahyu” menempati posisi sebagai salah satu pembentuk konstruk mengennai realitas, sebab wahyu diakui sebagai “ayat-ayat Tuhan” yang memberikan pedoman dalam pikiran dan tindakan seorang Muslim. Dalam konteks ini wahyu lalu menjadi unsur konstitutif di dalam paradigma Islam” begitu mas Kunto menjelaskan. Ada keuntungan yang dapat dipetik oleh ilmu (sosial-budaya) profetik dengan menempatkan wahyu sebagai salah satu sumber pengetahuan. Banyak hal-hal yang ada dalam wahyu merupakan paparan tentang apa yang terjadi di masa lampau yang tidak dapat lagi diketahui manusia, karena tidak ada jejak-jejaknya yang cukup jelas. Dengan adanya wahyu tersebut, berbagai hal yang terdapat di situ dapat menjadi petunjuk ke arah mana kegiatan keilmuan tertentu perlu diarahkan, seperti misalnya penelitian mengenai apa yang perlu dilakukan, yang hasilnya akan dapat mendatangkan manfaat optimal terhadap kehidupan manusia. Selanjutnya posisi wahyu sebagai sumber pengetahuan dalam ilmu (sosial-budaya) profetik adalah sama dengan pandangan mas Kunto, sebagaimana yang telah saya paparkan di depan. Walaupun itu semua 56 Paragima Profetik... sebenarnya masih belum cukup -karena saya merasa masih kurang rinci, namun untuk sementara paparan mengenai wahyu sebagai salah satu sumber pengetahuan saya cukupkan sampai di sini. e. Sunnah Rasulullah s.a.w. Mas Kunto tidak menyinggung tentang sunnah Rasulullah sebagai salah satu sumber pengetahuan. Saya memasukkannya, karena setahu saya dalam agama Islam, Al Qur’an tidak pernah dapat dipisahkan dari sunnah Rasulullah s.a.w. Ketika manusia di masa Rasulullah s.a.w. tidak dapat memahami dengan baik makna ayat-ayat yang turun, makna wahyu yang turun, mereka bertanya kepada Rasulullah s.a.w., karena melalui beliaulah wahyu tersebut turun. Pemahaman kita, tafsir kita mengenai berbagai ayat dalam Al Qur’an selalu awalnya bersumber dari penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Rasulullah s.a.w. atau perilaku dan tindakan beliau yang berdasarkan wahyu-wahyu tersebut. Dalam Islam, Al Qur’an dan Sunnah Rasulullah s.a.w. adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena Rasulullah s.a.w. adalah “Al Qur’an yang berjalan”, Al Qur’an yang mewujud dalam bentuk ucapan, perilaku dan tindakan. Jika kita menempatkan wahyu sebagai salah satu sumber pengetahuan, maka penjelasan tentang wahyu tersebut oleh penerima wahyu itu sendiri tentu tidak dapat diabaikan. 3. Asumsi Dasar tentang Objek Material Seperti halnya paradigma keilmuan yang lain, paradigma ilmu (sosial-budaya) profetik juga memiliki asumsi-asumsi tertentu berkenaan dengan obyek materialnya. Asumsi ini sebagian bisa sama, sebagian bisa berbeda. Asumsi-asumsi yang sejalan dengan asumsi ilmu pengetahuan biasa dapat kita ambil dari filsafat ilmu pengetahuan tersebut terutama filsafat positivisme, untuk ilmu alam profetik, sedang untuk ilmu sosial-budaya profetik asumsi-asumsi dasar tentang objek material ini dapat kita ambil dari berbagai paradigma yang berkembang dalam ilmu sosial-budaya biasa. Bab 2 57 Akan tetapi, mengambil dan menggunakan asumsi dasar dari paradigma-paradigma yang lain saja tentunya tidak cukup, karena hal itu akan membuat ilmu (sosial-budaya) profetik tidak ada bedanya dengan ilmu pengetahuan biasa. Jika kritik yang dilontarkan terhadap ilmu pengetahuan biasa adalah sifatnya yang sekuler, maka kelemahan inilah yang tidka boleh terulang dalam ilmu (sosial-budaya) profetik. Artinya, di sini harus dilakukan desekularisasi, yang berarti memasukkan kembali unsur sakral, unsur ke-Ilahian dalam ilmu (sosialbudaya) profetik. Bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah dengan menempatkan kembali segala objek material ilmu (sosial-budaya) profetik dan ilmuwan profetik dalam hubungan dengan Sang Maha Pencipta, Allah s.w.t. atau Tuhan Yang Maha Kuasa. Di sini perlu diasumsikan bahwa meskipun alam dan kehidupan manusia adalah sebuah realitas yang ada, namun realitas ini tidak muncul dengan sendirinya. Realitas ini ada Penciptanya. Oleh karena itu, kita tidak dapat memperlakukan realitas tersebut seenak kita, terutama seyogyanya kita tidak merusak realitas tersebut, kecuali kita memilki alasan-alasan yang dapat diterima berdasarkan patokan etika dan estetika tertentu. Menempatkan kembali realitas obyektif yang diteliti atau dipelajari sebagai ciptaan Allah Yang Maha Pencipta adalah apa yang oleh mas Kunto -menurut tafsir saya- disebut sebagai proses transendensi. Kata mas Kunto, “Bagi umat Islam sendiri tentu transendensi berarti beriman kepada Allah s.w.t.”. 4. Asumsi Dasar tentang Gejala yang Diteliti Asumsi dasar tentang gejala yang diteliti kiranya tidak terlalu berbeda dengan asumsi dasar tentang obyek material. Jika obyek material ilmu sosial profetik adalah manusia yang merupakan ciptaan Allah s.w.t. maka gejala yang diteliti juga dapat dipandang dengan demikian. Meskipun begitu, hal itu tidak berarti bahwa kita lantas tidak perlu mencari penjelasan tentang terjadinya atau munculnya gejala yang diteliti, karena hal itu juga tidak berlawanan dengan asumsi tersebut. 58 Paragima Profetik... Dalam ilmu-ilmu alam profetik ilmuwan meyakini bahwa alam dengan keseluruhan isinya merupakan hasil kreasi Sang Maha Pencipta. Jika kita ingin mengetahui mengenai hasil ciptaan ini tentunya kita akan dapat bertanya kepada Penciptanya. Akan tetapi tidak semua manusia dikaruniai kemampuan untuk melakukan komunikasi dengan Sang Pencipta, bahkan ketika komunikasi tersebut berhasil dibangun belum tentu pengetahuan mengenai semua hal di dunia akan diperoleh. Oleh karena itu, para nabi pun bukan merupakan orang yang paling tahu mengenai semua hal yang ada di muka bumi, yang ada dalam ciptaan Sang Maha Pencipta. Kisah mengenai Nabi Musa a.s. dengan nabi Khidir merupakan contoh yang sangat jelas mengenai hal ini. Yang jelas, dalam ilmu (social) profetik proses transendensi harus selalu dilakukan, karena ini merupakan penanda penting dari ilmu tersebut. Tanpa transendensi ini maka ilmu (social) profetik tidak akan banyak berbeda dengan ilmu-ilmu (social) di Barat. Mengenai transendensi dari gejala yang diteliti, para ilmuwan Muslim dapat mengembangkan lebih lanjut pemikiran ini, karena saya belum mempunyai kesempatan untuk merenungkan hal ini lebih mendalam. 5. Asumsi Dasar tentang Ilmu Pengetahuan Asumsi tentang ilmu profetik ini pada dasarnya mencakup sebagian yang telah saya paparkan di sini. Akan tetapi lebih khusus lagi, asumsi ini adalah pandangan mengenai hakikat dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Dalam filsafat ilmu di Barat, dikenal adanya dua pandangan yang berlawanan mengenai ilmu pengetahuan, yang masih terus diusahakan pendamaiannya. Pandangan pertama mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu adalah satu, sehingga tidak ada yang namanya ilmu pengetahuan alam (natural sci-ences) dan ilmu pengetahuan sosialhumaniora (budaya). Menurut pendapat ini meskipun ada perbedaan pada obyek material antara ilmu pengetahuan dan ilmu-ilmu socialbudaya, namun ilmu pengetahuan tidak perlu dibagi menjadi dua hanya karena objek materialnya berbeda. Bab 2 59 Pandangan ke dua mengatakan bahwa ilmu pengetahuan ada dua macam, yaitu ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial-budaya, karena obyek material masing-masing memang berbeda. Menurut pendapat ini, hakikat gejala social-budaya yang diteliti oleh ilmu-ilmu sosial-budaya berbeda dengan hakikat gejala-gejala yang dipelajari dalam ilmu alam. Oleh karena itu, ilmu-ilmu sosial-budaya tidak sama dengan ilmu-ilmu alam, karena dalam ilmu-ilmu sosial-budaya diperlukan metode-metode tertentu untuk mem-pelajari dan memahami gejala social-budaya yang berbeda dengan gejala alam. Ilmu-ilmu profetik dengan sendirinya memiliki pandangan yang berbeda juga dengan pandangan-pandangan di atas. Pencanangan ilmu profetik sebagai ilmu yang berbeda dengan ilm-ilmu yang lain menunjukkan adanya asumsi bahwa ilmu profetik berbeda dengan ilmuilmu yang telah ada, yakni ilmu alam dan ilmu social-budaya. Dalam ilmu profetik gejala yang dipelajari ada yang berbeda dengan gejala yang dipelajari oleh ilmu-ilmu yang lain, yakni wahyu, dan ada perspektif (obyek formal) yang berbeda, yakni wahyu juga. Elemen wahyu inilah yang membedakan ilmu-ilmu profetik dengan il-mu-ilmu yang lain. Mengenai hal ini diperlukan paparan yang lebih mendalam, yang tidak akan saya lakukan di sini. 6. Asumsi Dasar tentang Ilmu Sosial dan/atau Alam Profetik Selain memiliki persamaan-persamaan, ilmu alam maupun ilmu sosial-budaya pro-fetik juga memiliki perbedaan-perbedaan pada asumsinya, sehingga ada perbedaan antara ilmu social-budaya profetik dengan ilmu alam profetik. Asumsi-asumsi ini seba-gian besar berasal dari ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial-budaya yang sudah ada, sebagian lagi tidak. Asumsi-asumsi yang menjadi landasan ilmu-ilmu social-budaya profetik sebagian berasal dari ilmu-ilmu sosial-budaya biasa, untuk membedakannya dengan ilmu-ilmu alam, dan sebagian lagi berasal dari Paragima Profetik... 60 ilmu profetik, untuk membedakannya dengan ilmu-ilmu social-budaya yang tidak profetik. 7. Asumsi Dasar tentang Disiplin Profetik Yang dimaksud dengan disiplin di sini adalah cabang ilmu pengetahuan. Disiplin profetik adalah cabang ilmu pengetahuan tertentu dalam ilmu pengetahuan empiris biasa, tetapi ditambah dengan ciri profetik. Disiplin profetik ini tentu saja merupakan disiplin yang berbeda, walaupun masih ada persamaan dengan disiplin ilmu pengetahuan biasa. Disiplin profetik ini dapat kita bangun dari disiplin ilmu biasa, sehingga kita dapat memiliki ilmu kedokteran profetik, ilmu kehutanan profetik, ilmu teknik profetik, ilmu farmasi profetik, sosiologi profetik, ilmu hukum profetik, psikologi profetik, antropologi profetik, dan seterusnya. Asumsi-asumsi dasar disiplin profetik ini tentu saja sebagian akan sama dengan asumsi dasar disiplin ilmu pengetahuan yang ada, tetapi sebagian yang lain tentu akan berbeda. Oleh karena masing-masing disiplin memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri, ma-ka ekspresi ciri profetik ini juga berbeda-beda dalam masing-masing disiplin, tetapi di situ tetap ada keprofetikan yang diturunkan dari sesuatu keprofetikan yang umum. Sebagai contoh, paradigma kedokteran profetik misalnya, sebagian asumsi dasarnya akan berasal dari ilmu kedokteran pada umumnya, ilmu kedokteran empiris, tetapi sebagian lagi berasal dari asumsi dasar yang ada dalam ilmu profetik, yang tidak terdapat dalam ilmu kedokteran empiris. D. Etos Paradigma Profetik Yang dimaksud dengan etos di sini adalah perangkat nilai atau nilai-nilai yang mendasari perilaku suatu golongan atau kelompok manusia. Sebagian paradigma dalam ilmu pengetahuan biasa memiliki perangkat nilai atau etos yang berlainan dengan perangkat nilai paradigma yang lain. Perangkat nilai paradigma ilmu pengetahuan yang Bab 2 61 transformatif, yang ditujukan untuk menghasilkan perubahan dalam kehidupan kemasyarakatan dan kebudayaan, berbeda dengan perangkat nilai ilmu pengetahuan yang lebih akademis, yang ditujukan terutama untuk memahami dan menjelaskan berbagai gejala dalam kehidupan manusia, walaupun sebagian juga ada yang ditujukan untuk transformasi sosial-budaya. Etos ilmu profetik dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut ini. 1. Basis Semua Etos: Penghayatan Sebagaimana telah saya katakan, unsur yang sangat membedakan antara ilmu (sosial-budaya) profetik dengan yang bukan adalah pada unsur transendensinya. Unsur transendensi ini dalam kehidupan ilmiah diwujudkan dalam bentuk penghayatan. Yang dimaksud dengan penghayatan di sini adalah pelibatan pikiran dan perasaan seseorang pada sesuatu yang diyakininya atau disukainya. Kalau dalam beragama penghayatan tersebut diwujudkan dalam peribadatan, dalam dunia keilmuan (sosial-budaya) hal tersebut diwujudkan dalam kegiatan keilmuan sehari-hari. Penghayatan aktivitas keilmuan ini merupakan hal yang tidak mudah dilakukan, terutama apabila tujuan dari aktivitas tidak sangat sejalan dengan tujuan dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Paradigma ilmu profetik menekankan pada penghayatan, karena aktivitas keilmuan di sini tidak lagi hanya sekedar untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi dan material, tetapi lebih dari itu. Aktivitas ini merupakan ekspresi atau perwujudan dari etos dasar dalam paradigma profetik, yakni pengabdian. Paragima Profetik... 62 Skema 4. Etos Ilmu Profetik Basis Etos Ilmu Profetik Etos Kerja Keabdian untuk untuk untuk untuk untuk Etos Kerja Keilmuan pengembangan unsur pengembangan paradigma pengembangan sistem pengetahuan Penghayatan Allah s.w.t Ilmu Diri Sendiri Sesama Alam Semesta Etos Kerja Kemanusiaan kejujuran ketelitian / keseksamaan kekritisan ketawadhu’an (penghargaan) Etos Kerja Kesemestaan perlindungan pemeliharaan pemanfaatan pengembangan 2. Etos: Pengabdian Hal yang sangat penting berkenaan dengan ilmu (sosial-budaya) profetik adalah perangkat nilai yang ada dalam ilmu ini. Saya berpendapat bahwa nilai-nilai ini mempunyai nilai inti, yang menjadi dasar bagi nilai-nilai yang lain. Dalam hal ini saya berpendapat bahwa etos kerja utama dari ilmu ini adalah “beribadah”, yang dalam hal ini saya tafsirkan sebagai “pengabdian”, penghambaan. Penghambaan ini tentu ada tingkatannya dan jenisnya. Penghambaan atau pengabdian ini dalam Islam berupa rukun Islam. Dalam dunia keilmuan (sosialbudaya) profetik etos pengabdian ini ditransformasikan menjadi pengabdian pada lima hal, yakni pada (a) Allah; (b) Pengetahuan; (c) diri-sendiri; (d) sesama dan (e) alam. a. Untuk Allah s.w.t. Pengabdian kepada Allah dalam aktivitas keilmuan adalah meniatkan semua aktivitas keilmuan sehari-hari untuk Allah s.w.t semata, dalam rangka memuliakan Allah s.w.t., dalam rangka mewujudkan segala perintah-perintahnya dan mengikuti segala larangannya. Ini merupakan transformasi rukun Islam yang pertama, yaitu membaca kalimat syahadat. Pengakuan atas Allah s.w.t. sebagai satu-satunya Tuhan yang layak disembah, tempat mengabdi, dan Bab 2 63 pengakuan atas kerasulan Muhammad s.a.w, bahwa Muhammad s.a.w. adalah utusan Allah s.w.t. b. Untuk Pengetahuan (Ilmu) Pengabdian untuk ilmu dalam aktivitas keilmuan adalah meniatkan aktivitas keilmuan sehari-hari untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan keilmuan. Akan tetapi pengembangan ilmu pengetahuan ini tetap harus ditempatkan sebagai bagian atau unsur dari aktivitas untuk mengabdi kepada Allah s.w.t. itu sendiri. Di sini ilmuwan melakukan aktivitas keilmuan dengan niat untuk mengabdi atau sebagai perwujudan dari niat untuk mengabdi kepada Allah s.w.t. Pengabdian untuk ilmu merupakan transformasi dari rukun Islam kedua, yakni sholat. Dalam sholat seseorang melakukan konsentrasi untuk berdialog dengan Tuhannya. Ini seperti sebuah proses perenungan dalam aktivitas keilmuan. Sholat adalah sebuah aktivitas ibadah yang penuh perenungan, yang akan membuat pemahaman seseorang tentang diri, kehidupan dan Tuhannya akan semakin bertambah. c. Untuk Diri Sendiri Selanjutnya aktivitas keilmuan juga dilakukan dalam rangka untuk keberlangsungan hidup diri-sendiri. Di sini aktivitas keilmuan adalah juga merupakan satu bentuk atau wujud dari mata pencaharian, yang penting untuk keberlangsungan hidup diri-sendiri. Aktivitas keilmuan di sini merupakan transformasi dari rukun Islam puasa. Puasa adalah sebuah ibadah yang paling tersembunyi, yang dapat ditafsirkan sebagai sebuah ibadah yang sangat pribadi. Aktivitas keilmuan juga merupakan aktivitas yang bisa dilakukan secara sendirian, sebagaimana halnya ketika seseorang merenungkan masalah-masalah keilmuan tertentu. d. Untuk Sesama Aktivitas keilmuan juga bisa bersifat sosial, yang mempunyai dampak terhadap kehidupan sesama manusia. Ini merupakan transformasi dari rukun Islam mengeluarkan zakat, yang juga Paragima Profetik... 64 berdampak pada kehidupan manusia lain. Zakat adalah kegiatan ibadah yang bersifat menguntungkan orang lain secara material, sedang untuk diri sendiri bersifat spiritual. Transformasi zakat ini dalam kehidupan ilmiah adalah pengajaran atau pemberian ilmu, yang kemudian akan menguntungkan orang lain yang diberi ilmu. Dalam konteks keilmuan profetik seorang ilmuwan yang memberikan bimbingan, mengajar, ceramah, memberikan pelatihan, yang sifatnya cuma-cuma atau tidak menarik pembayaran dari orang yang diberi pengetahuan, dapat dikatakan sedang melakukan kegiatan memberikan zakat, karena di sini penerima zakat -yaitu orang yang menerima pengetahuan- tidak perlu memberi imbalan kepada orang yang memberinya ilmu. Kegiatan seperti ini tentunya memberikan manfaat kepada sesama manusia, karena mereka yang mendapat pengetahuan kemudian menjadi orang yang tahu, yang dengan pengetahuan tersebut dia akan dapat melakukan sesuatu yang berguna. e. Untuk Alam Aktivitas keilmuan juga mempunyai dampak terhadap kehidupan yang lebih luas lagi, yakni alam di sekeliling manusia. Aktivitas keilmuan yang seperti ini merupakan aktivitas keilmuan dengan dampak yang paling luas. Ini merupakan transformasi dari rukun Islam naik haji, yang memang memiliki dampak sosial-budaya yang paling luas. 3. Etos Kerja Keilmuan Selain etos pengabdian, paradigma profetik tentunya juga mengenal etos kerja keilmuan, yakni semangat untuk melakukan sesuatu yang akan bemanfaat bagi ilmu pengetahuan itu sendiri. Oleh karena inti dari ilmu pengetahuan adalah paradigma dan sebuah paradigma selalu terdiri dari berbagai unsur, maka aktivitas yang dapat dilakukan untuk mendatangkan manfaat bagi ilmu pengetahuan tersebut tidak lain adalah mengembangkan unsur-unsur paradigma yang sudah ada, mengembangkan paradigma-paradigma baru, dan mengembangkan sistem pengetahuan yang ada. Bab 2 65 a. Pengembangan Unsur Paradigma Pengembangan unsur paradigma di sini dapat dilakukan melalui dua hal, yakni (a) menambahkan sub-sub-unsur baru atau konsep-konsep baru dalam unsur paradigma yang ada, atau (b) menambahkan pemaknaan-pemaknaan baru terhadap konsep-konsep yang sudah ada, atau (c) menggantikan unsur paradigma yang lama dengan unsur baru yang lebih tepat. Jika dua hal ini dilakukan dengan baik, bukan tidak mungkin sebuah paradigma baru akan dapat dibangun. b. Pengembangan Paradigma Baru Semangat mendatangkan manfaat bagi ilmu pengetahuan juga dapat berupa pengembangan paradigma baru, yang berarti membangun sebuah cara berfikir baru. Dalam hal ini unsur-unsur paradigmanya tetap sama, tetapi isi dari unsur-unsur tersebut berbeda. Melalui pengembangan paradigma baru ini seorang ilmuwan profetik dapat memberikan sumbangan yang maksimal terhadap kehidupan manusia dan perkembangan ilmu pengetahuan. c. Pengembangan Sistem Pengetahuan Etos kerja keilmuan profetik juga dapat ditujukan untuk mengembangkan sistem pengetahuan yang lebih luas, yang mencakup lebih banyak paradigma lagi. Hal ini memang tidak mudah dilakukan, akan tetapi para ilmuwan profetik dapat menjadikannya sebagai etos kerja. Pengembangan sistem pengetahuan dalam arti yang luas akan memudahkan para ilmuwan untuk beraktivitas dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga berbagai pembaharuan pengetahuan dapat dilakukan. 4. Etos Kerja Kemanusiaan Dalam pandangan paradigma profetik, aktivitas ilmiah seorang ilmuwan pada dasarnya juga merupakan aktivitas kemanusiaan. Seorang ilmuwan profetik juga perlu peduli terhadap kemanusiaan. Berdasarkan atas kedekatannya, kemanusiaan ini tentu saja berjenjang. Dalam konteks Paragima Profetik... 66 keilmuan, maka mereka yang paling dekat dengan seorang ilmuwan adalah sesama ilmuwan. Inilah lingkungan sosial yang utama. Terhadap mereka ini, terhadap sesama kolega paradigma profetik juga memiliki etos kerja tertentu, yang disebut etos kerja kemanusiaan. Etos kerja kemanusiaan ini paling tidak ada empat, yaitu (a) kejujuran; (b) keseksamaan/ketelitian; (c) kekritisan dan (d) ketawadhu’an (penghargaan). a. Kejujuran Seorang ilmuwan profetik harus selalu jujur, baik terhadap dirisendiri maupun terhadap orang lain. Dalam konteks keilmuan profetik, kejujuran ini bisa berkaitan dengan pengajaran (dalam konteks ajarmengajar), berkaitan dengan penelitian, berkaitan dengan hasil penelitian, berkenaan dengan kerjasama sesama peneliti, dan sebagainya. Kejujuran juga harus selalu dijaga dalam pengutipan pemikiran, hasil penelitian, per-nyataan-pernyataan ilmuwan lain, dan sebagainya. b. Keseksamaan / Ketelitian Seorang ilmuwan profetik juga perlu menganut nilai keseksamaan atau ketelitian. Artinya, dalam berbagai kegiatan keilmuan (pengajaran, penelitian, pengabdian masya-rakat) seorang ilmuwan profetik harus selalu teliti, cermat dan berhati-hati. Kehati-hatian ini harus selalu diperhatikan dalam setiap kegiatan ilmiah, sampai pada hal-hal yang sangat kecil, seperti misalnya menulis nama ilmuwan lain, judul buku, halamana jurnal, dan sebagainya c. Kekritisan Seorang ilmuwan profetik juga harus selalu kritis. Artinya, berusaha sedapat mungkin melihat kelemahan-kelemahan tetapi sekaligus juga kelebihan-kelebihan pada apa yang telah dilakukan dan dihasilkan oleh ilmuwan lain. Kekritisan ini harus dilandaskan pada semangat kejujuran dan demi kebaikan bersama, atau demi melakukan yang lebih baik dan mencapai hasil yang lebih baik lagi. Bab 2 67 d. Ketawadhu’an (Penghargaan) Seorang ilmuwan profetik juga harus selalu rendah hati agar dapat menghargai kerja dan karya orang lain, ilmuwan lain. Penghargaan ini sebaiknya disampaikan secara terang-terangan, baik lisan maupun tertulis, misalnya dengan menyampaikan apa yang benar dan disetujui dari pendapat ilmuwan lain, apa yang baru dan bermanfaat dari teori yang dikemukakan ilmuwan lain, dan sebagainya. Dengan adanya saling menghargai pekerjaan, hasil karya dan pandangan ilmuwan lain, maka kerjasama di kalangan ilmuwan profetik akan dapat berjalan dengan baik pula. E. Model Paradigma Profetik Unsur paradigma setelah asumsi-asumsi dasar dan etos adalah model. Model atau analogi di sini tentu saja diambil dari ranah keagamaan, agama Islam. Ada banyak model dalam ranah tersebut yang dapat dipakai untuk melakukan kajian keilmuan, namun sehubungan dengan bangunan paradigma di sini, model yang dapat dipakai untuk sementara ini adalah rukun iman dan rukun Islam, karena dua rukun inilah yang mendasari kehidupan keagamaan dalam agama Islam. Jika kita umpamakan kehidupan keilmuan profetik adalah seperti kehidupan keagamaan Islam, maka di situ perlu ada dua rukun tersebut. Akan tetapi oleh karena ranahnya berbeda, maka model tersebut perlu ditransformasikan agar dapat sesuai dengan konteks ranahnya. 1. M o d e l (Struktur) Transformasinya Rukun Iman dan Rukun iman dalam agama Islam terdiri dari iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi, kepada hari kiamat dan kepada takdir. Iman yang pertama adalah iman kepada Allah s.w.t. “Beriman” di sini dapat dimaknai sebagai membangun relasi dengan yang diimani. Relasi antara manusia dengan Allah s.w.t. adalah relasi antara seorang hamba dengan Penciptanya. Hamba di sini harus mengabdikan diri kepada sang Pencipta. Paragima Profetik... 68 Dalam konteks keagamaan Allah juga dapat diyakini sebagai sumber pengetahuan, sehingga dalam konteks keilmuan profetik pengabdian seorang ilmuwan adalah kepada ilmu pengetahuan. Tentu konsep pengabdian di sini tidak sama persis maknanya dengan pengabdian dalam konteks kehidupan beragama, karena ilmu bukanlah sebuah konsep sebagaimana halnya Allah s.w.t. Pengabdian di sini perlu sebaiknya dimaknai sebagai ketekunan seorang ilmuwan menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang ilmuwan. Pengabdian di sini lebih merupakan sebuah metafor, yang berbeda maknanya dengan pengabdian dalam pengabdian kepada Allah s.w.t. Transformasi yang pertama dari rukun iman adalah sebagai berikut: Manusia Ilmuwan pengabdian pengabdian Allah s.w.t. Ilmu pengetahuan Rukun iman yang kedua adalah beriman kepada malaikat. Dalam ranah kehidupan agama, malaikat dikatakan sebagai sahabat orang beriman. Dalam konteks kehidupan ilmuwan profetik malaikat ini dapat ditafsirkan sebagai sesama ilmuwan, dan hubungan yang ada di antara mereka haruslah hubungan persahabatan, bukan hubungan persaingan, apalagi permusuhan. Transformasi rukun iman kedua dalam konteks ilmu profetik adalah: Manusia Ilmuwan persahabatan persahabatan Malaikat Kolega Rukun iman yang ketiga adalah beriman kepada Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah s.w.t. kepada manusia melalui para nabinya. Dalam kehidupan ilmuwan profetik kitab ini tidak lain adalah kitabkitab juga, tetapi kitab-kitab keilmuan, serta berbagai tu-lisan ilmiah, yang harus mereka baca dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan, dan merupakan bentuk dari pengabdian mereka kepada ilmu pengetahuan. Transformasi rukun iman ketiga pada konteks ilmu profetik adalah: Manusia Ilmuwan pembacaan pembacaan Kitab Kitab Ilmiah Bab 2 69 Rukun iman yang keempat adalah beriman kepada para nabi yang diutus oleh Allah s.w.t. Bagi orang beriman para nabi ini adalah guru, tetapi juga sahabat. Dalam konteks keilmuan profetik para nabi dapat ditafsirkan sebagai para ilmuwan terkenal, yang selain sahabat para ilmuwan, mereka ini juga merupakan tokoh-tokoh yang banyak diikuti pemikiran-pemikirannya. Transformasi rukun iman keempat dalam konteks ilmu profetik adalah: Manusia Ilmuwan perguruan + persahabatan perguruan + persahabatan Nabi Tokoh Rukun iman kelima adalah beriman kepada hari kiamat. Hari kiamat dapat ditafsirkkan berbagai macam. Salah satu tafsir yang dapat diberikan adalah bahwa hari kiamat merupakan hari akhir dari sesuatu. Hari kiamat tidak ada yang mengetahui kapan tibanya, tetapi diketahui tanda-tandanya. Di sini terkandung makna bahwa manusia dapat mengetahui kapan sesuatu akan berakhir, dan kemudian berusaha menundanya, bukan meniadakannya. Dalam konteks keilmuan profetik, hari kiamat dapat ditafsirkan sebagai akhir dari sesuatu, apakah itu suatu gejala tertentu, teori tertentu, ajaran tertentu, dan sebagainya. Sehubungan dengan itu ilmuwan profetik dapat melakukan langkahlangkah atau upaya untuk menunda tibanya saat akhir tersebut. Jika berhubungan dengan teori, penundaan tersebut adalah upaya-upaya ntuk memperbaiki teori tersebut; jika berhubungan dengan suatu masyarakat penundaan tersebut adalah dengan melakukan perbaikanperbaikan atas masyarakat tersebut. Transformasi rukun iman kelima dalam konteks ilmu profetik adalah: Manusia Ilmuwan penundaan penundaan Hari Kiamat Akhir Rukun iman keenam adalah iman kepada takdir. Takdir merupakan suatu hal yang diluar kemampuan manusia untuk memahaminya. Dalam konteks keilmuan profetik hal ini sebuah pengakuan bahwa suatu cabang ilmu pengetahuan, atau suatu paradigma tidak akan dapat menyelesaikan masalah. Dari salah satu prinsip penting dalam filsafat 70 Paragima Profetik... positif tentang ilmu pengetahuan, pengakuan bahwa kemampuan dan pengetahuan manusia terbatas sifatnya, merupakan salah satunya. Pengakuan ini sekaligus menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan mengakui keterbatasan manusia untuk mengerti dan memahami semua hal. Transformasi rukun keenam dalam konteks ilmu profetik adalah: Manusia Ilmuwan penerimaan penerimaan 2. M o d e l (Struktur) Transformasinya Takdir Ilmu Terbatas Rukun Islam dan Seperti halnya rukun iman, rukun Islam sebagai basis dari kehidupan beragama juga perlu ditransformasikan dalam konteks kehidupan dan aktivitas keilmuan profetik. Rukun Islam terdiri dari lima jenis rituil atau tindakan keagamaan yaitu; (1) membaca dua kalimat syhadat; (2) mengerjakan sholat lima kali sehari dalam waktu yang telah ditentukan; (3) mengerjakan puasa dalam bulan Ramadhan; (4) mengeluarkan zakat; (5) mengerjakan ibadah haji, jika mampu. Masingmasing rukun ini perlu ditransformasikan dalam kehidupan keilmuan profetik. Kalau dalam kehidupan beragama rukun yang pertama, -membaca kalimat syaha-dat-, seorang yang beriman menyatakan secara eksplisit pengakuannya atas Allah sebagai satu-satunya Dzat Yang Patut Disembah, dan Muhammad adalah utusanNya, maka dalam kehidupan keilmuan profetik syahadat ini ditransformasikan pada keyakinan tentang ilmu, tentang pengetahuan, dan manfaatnya, dan bahwa Allah adalah sumber pengetahuan, dan Allah telah menurunkan wahyu. Syahadat keilmuan di sini adalah pengakuan bahwa wahyu adalah juga sumber pengetahuan, yang lebih tinggi kualitasnya daripada pengetahuan yang manapun, karena wahyu datang langsung dari sumber pengetahuan itu sendiri, pemilik pengetahuan itu sendiri, yaitu Allah s.w.t. Bab 2 71 Rukun Islam kedua adalah menjalankan sholat. Dalam sholat seseorang merenung, mengingat Allah s.w.t. Dalam kehidupan keilmuan profetik, transformasi rukun ini berupa kontemplasi keilmuan. Merenungkan tentang masalah-masalah yang sedang diteliti mencoba mencari jawabnya secara serius. Dari kegiatan ini seorang ilmuwan akan mendapat inspirasi. Rukun Islam ketiga adalah mengerjakan puasa. Puasa dikerjakan selama satu bulan dan selama puasa itu seorang Muslim juga dianjurkan untuk banyak merenung, banyak membaca kitab, di samping melakukan kegiatan yang lain. Transformasi dari kegiatan puasa, yang berarti juga menahan diri dari melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, dalam konteks keilmuan adalah penelitian. Selama melakukan penelitian, seorang ilmuwan seolah-olah sedang bertapa, berpuasa, menahan diri dari melakukan hal-hal yang biasa dilakukan. Dari kegiatan penelitian ini seorang ilmuwan akan memperoleh temuan-temuan ilmiah dan melakukan pengembangan ilmu pengetahuan. Rukun Islam yang keempat adalah mengeluarkan zakat, yang berarti memberikan kepada orang lain sebagian dari harta yang dimiliki. Dalam konteks keilmuan profetik, harta yang dimiliki oleh seorang ilmuwan adalah pengetahuan, ilmu pengetahuan. Zakat dalam konteks tersebut adalah memberikan pengetahuan kepada orang lain, yaitu mengajar, memberikan ceramah-ceramah, memberikan pelatihan, dan sebagainya. Rukun Islam yang kelima adalah menjalankan ibadah haji ke Mekkah. Di sini seorang Muslim melakukan perjalanan selama beberapa hari, melakukan ibadah haji selama beberapa hari, dan bertemu dengan ratusan, ribuan Muslim yang lain. Arena haji adalah sebuah arena pertemuan Muslim seluruh dunia, dan dari pertemuan ini bisa terjadi saling tukar pendapat, tukar pengalaman, tukar pengetahuan. Dalam konteks keilmuan profetik, transformasi ibadah naik haji adalah pertemuan-pertemuan internasional selama beberapa hari di mana terjadi tukar pendapat, tukar pandangan, yang semakin meningkatkan Paragima Profetik... 72 kualitas keilmuan seseorang, sebagaimana halnya ibadah naik haji yang meningkatkan kualitas keagamaan seorang Muslim. Transformasi lima rukun Islam dalam konteks keilmuan profetik di atas dapat digambarkan sebagai berikut. Syahadat Syahadat Keilmuan Wahyuisme (Revelationism) Rasionalisme Empirisisme : Sholat Perenungan Inspirasi : Puasa : Zakat : Haji Penelitian Pengajaran Pertemuan Temuan Penyebaran Pertemuan F. Implikasi Epistemologi Profetik Basis epistemologis yang saya paparkan di atas tentu punya implikasi terhadap unsur-unsur lain dalam paradigma profetik, yang secara logika muncul setelah unsur-un-sur di atas, yaitu unsur (a) masalah yang ingin dan perlu diteliti oleh ilmu (sosial-budaya) profetik; (b) perangkat konseptual yang digunakan serta definisinya; (c) metode penelitiannya; (d) metode analisisnya (e) teori-teori yang dihasilkan dan (f) representasi yang digunakan, yang disajikan oleh ilmu (sosial-budaya) profetik. Jalur implikasi logis ini tidak sederhana, karena ada yang bersifat langsung ada pula yang tidak. Unsur etos, nilai-nilai, misalnya bisa secara langsung berimplikasi atau turut menentukan metode dan siasat penelitian yang digunakan, ataupun representasi yang disajikan oleh peneliti. Demikian pula halnya implikasi dari asumsi bahwa wahyu merupakan salah satu sumber pengetahuan. Ada banyak implikasi yang muncul dari asumsi dasar ini, mulai dari implikasi permasalahan sampai ke implikasi representasi. Implikasi dari asumsi dasar, etos dan model paradigma profetik dapat digambarkan dalam skema berikut ini. Bab 2 73 Skema 5. Implikasi Epistemologi Profetik Implikasi Permasalahan Implikasi Konseptual Implikasi Metodologis Penelitian Implikasi Epistemologi Profetik Implikasi Metodologis Analisis Implikasi Teoritis Implikasi Representasional (Etnografis) 1. Implikasi Permasalahan Yang dimaksud dengan implikasi permasalahan adalah masalahmasalah yang muncul sebagai akibat dari diterimanya asumsi-asumsi dasar tertentu, nilai-nilai atau etos tertentu. Sebagai contoh, dengan asumsi bahwa wahyu merupakan sumber ilmu pengetahuan, maka kumpulan wahyu -yakni Al Qur’an- akan menjadi salah satu sumber untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan atau hipotesa-hipotesa untuk diteliti lebih lanjut. Selain itu, karena ilmu profetik juga diinginkan menjadi ilmu yang transformatif, maka pemilihan masalah-masalah untuk penelitian tentunya juga yang akan punya effek transformatif juga. Permasalahan ini bisa dimunculkan dari Al Qur’an dan sunnah Rasulullah, bisa dari permasalahan sehari-hari tetapi yang dianggap paling mendesak atau penting untuk diteliti dan dicarikan penyelesaiannya, bisa pula dari transformasi masalah-masalah yang ada dalam Al Qur’an dan sunnah Rasulullah. 2. Implikasi Konseptual Implikasi konseptual adalah berbagai konsep yang muncul sebagai implikasi dari penggunaan wahyu sebagai salah satu sumber pengetahuan, sumber inspirasi. Dalam hal ini berbagai istilah yang ada dalam Al Qur’an dan hadist kemudian dapat dan perlu didefinisikan, dijelaskan dan dioperasionalisasikan sehingga dapat digunakan dalam penelitian. Implikasi konseptual juga bisa muncul dari pemilihan masalah-masalah baru untuk diteliti. Data baru yang dihasilkan oleh 74 Paragima Profetik... penelitian ini akan membutuhkan konsep-konsep baru untuk menggunakannya dengan baik. 3. Implikasi Metodologis Penelitian Pemilihan masalah-masalah tertentu, penggunaan konsep-konsep yang baru, biasanya akan mempunyai implikasi terhadap metode penelitian yang akan digunakan. Sangat mungkin akan muncul metode-metode penelitian baru yang muncul sebagai akibat dari digunakannya konsep tertentu, atau dipilihnya asumsi-asumsi tertentu sebagai basis penelitian. Jika implikasi-implikasi ini diperhatikan dan diikuti secara serius, tentu akan muncul penelitian-penelitian dengan menggunakan model dan asumsi tertentu. Dengan begitu maka ilmu pengetahuan akan dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat. 4. Implikasi Metodologis Analisis Di sini saya membedakan metode penelitian, yakni metode pengumpulan data, de-ngan metode analisis data, karena masing-masing memang membutuhkan metode-metode yang berbeda, serta merupakan tahap-tahap yang berbeda dalam proses penelitian. Proses pengumpulan data biasa dilakukan di perpustakaan, di laboratorium dan di lapangan, sedang proses analisis data bisa dilakukan di perpustakaan, di rumah di laboratorium atau di tempat lain yang memungkinkan. Metode pengumpulan data berbeda dengan metode analisis data. Implikasi metodologis dapat terjadi pada metode analisis ini, dan ini bisa dikarenakan oleh masalah yang diteliti, oleh konsep yang digunakan atau oleh jenis data yang berbeda. Peneliti harus memperhatikan implikasi ini baik-baik, agar analisis data dapat dilakukan dengan baik dan benar. 5. Implikasi Teoretis Implikasi teoretis tentu akan ada, karena tidak mungkin perubahan atau pergantian masalah dan asumsi dasar tidak mempunyai implikasi Bab 2 75 teoretis. Implikasi inilah saya kira yang akan merupakan implikasi yang sangat penting, jika bukan yang terpenting, dari paradigma profetik. Munculnya teori-teori baru akan merupakan sumbangan yang sangat penting yang dapat diberikan oleh ilmu-ilmu profetik. 6. Implikasi Representasional (Etnografis) Implikasi representasional merupakan implikasi yang terjadi pada ranah representasi atau penyajian teori. Pada ilmu-ilmu alam, ranah representasi ini mungkin tidak begitu penting, karena terdapat pola yang agak baku dalam cara representasinya. Tidak demikian halnya pada ilmu-ilmu sosial-budaya. Oleh karena asumsi dasar, etos dan model yang berbeda, maka representasi dari apa yang telah dihasilkan, yakni data dan teori akan berbeda pula. Di sini ilmu-ilmu sosial-budaya profetik memiliki potensi besar untuk menyajikan hal-hal yang baru, yang dapat membuka wawasan baru kehidupan manusia. G. Implikasi Paradigma Profetik Berkenaan dengan implikasi dari ilmu (sosial-budaya) profetik yang dikemukakannya, mas Kunto mengatakan bahwa ilmu ini tentunya akan mempunyai implikasi sosial transformatif yang penting. Mas Kunto mengakui bahwa paradigma Islam mempunyai implikasi transformatif pada level individual, tetapi dia tampaknya lebih tertarik untuk membicarakan mengenai transformasi sosialnya, karena dia adalah ahli sejarah sosial. Akan tetapi, hal ini justru membuat potensi transformatif paradigma Islam menjadi tidak optimal. Menurut hemat saya, paradigma Islam tersebut harus dikupas potensi transformatifnya, baik pada tingkat individu, keluarga ataupun masyarakat. 1. Transformasi Individual Sebagaimana telah saya paparkan di atas, salah satu basis etos paradigma profetis adalah penghayatan. Penghayatan ini berlangsung pada tataran individual. Oleh kare-na itu, ilmu (sosial-budaya) profetik 76 Paragima Profetik... tentunya punya effek transformatif bukan hanya pada tataran sosialbudaya sebagaimana yang dibayangkan oleh mas Kunto, tetapi juga pada tataran individual. Di sinilah ilmu (sosial-budaya) profetik juga dapat mencakup cabang ilmu seperti psikologi. Transformasi individual ini bisa dua macam, karena ilmu profetik bisa menghasilkan transformasi pada diri ilmuwan profetik, atau pada pada individu yang menjadi kajian ilmu profetik tertentu, yaitu psikologi dan kedokteran. Ilmu profetik kedokteran akan melahirkan transformasi individual pada ranah atau bidang ragawi (physical), sedang ilmu psikologi profetik akan menghasilkan transformasi pada ranah kejiwaan(psychical). Di lain pihak keterlibatan seorang ilmuwan dalam kegiatan keilmuan dengan semangat profetik, dengan etos profetik, akan membuat ilmuwan itu sendiri mengalami perubahan-perubahan tertentu. Transformasi di sini tetnu saja merupakan transformasi pada ranah kejiwaan, yang menyangkut pikiran dan perasaan. Transformasi individual sebagai dampak dari paradigma profetik menurut hemat saya tidak kalah penting dengan effek transformatif pada tataran sosial. Gagasan mengenai ini perlu dikembangkan lebih lanjut, karena mas Kunto belum banyak memperhatikan dan membahasnya. 2. Transformasi Sosial (Kolektif) Mengenai transformasi sosial ini, mas Kunto telah membahasnya cukup panjang-le-bar, walaupun belum tuntas dan masih perlu dikembangkan lagi. Seperti halnya transformasi pada ranah individu, transformasi kolektif atau sosial ini juga bisa terjadi di kalangan ilmuwan, bisa pula di kalangan warga masyarakat yang lebih luas. Masing-masing transformasi akan memiliki corak yang berbeda. Di kalangan ilmuwan, transformasi dapat -dan seharusnya-terjadi di kalangan pela-ku ilmu profetik ini, yakni di kalangan ilmuwannya. Transformasi ini bisa diawali dari tataran pandangan hidup, yang Bab 2 77 kemudian mewujud menjadi suatu gaya hidup -gaya hidup ilmuwan profetik-, dan selanjutnya pada karya-karya mereka. Jika ini terjadi, maka transformasi kemudian bisa menurun kepada lingkungan yang lebih luas, yakni pada kalangan anak didik mereka. Transformasi berikutnya adalah transformasi di kalangan masyarakat, yang merupakan dampak dari kehadiran para ilmuwan profetik dengan pandangan, keyakinan dan gaya hidup mereka, atau merupakan dampak dari hasil-hasil kajian yang mereka lakukan. Kajiankajian ilmu profetik akan dapat memberikan dampak transformatif sosial yang lebih luas bilamana hasil-hasil kajian ini selalu dipublikasikan dan disosialisasikan ke tengah masyarakat dengan cara yang sistematis dan terencana dengan baik. H. Penutup Dalam makalah ini saya telah mencoba memaparkan sebagian pandangan saya mengenai ilmu (sosial-budaya) profetik. Keterbatasan waktu dan ruang membuat saya belum dapat mengembangkan pemikiran tentang hal-hal di atas secara lengkap dan utuh. Meskipun demikian, di sini saya telah memberikan sebuah model atau kerangka paradigma dengan unsur-unsur yang menurut hemat saya sudah lengkap. Berdasarkan kerangka paradigma inilah saya menjelaskan isi epistemologi profetik, yang men-cakup asumsi-asumsi dasar, etos dan model-model yang mendasarinya. Isi elemen-elemen lain dari paradigma profetik ini, yang merupakan implikasi dari basis epistemologisnya bisa berbeda antara disiplin profetik satu dengan yang lain, sehingga sebaiknya diisi oleh ilmuwan-ilmuwan lain dari masing-masing disiplin. Di situlah para kolega ilmuwan dapat berpartisipasi mengembangkan gagasan mengenai ilmu (sosial-budaya) profetik, agar paradigma profetik di sini memiliki dampak yang lebih luas dan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada kemajuan peradaban manusia...Dan Allahlah Yang Maha Tahu...... 78 Paragima Profetik... BAB 3 LANDASAN ONTOLOGI ILMU HUKUM PROFETIK M. Syamsudin A. Pengantar Dalam perspektif filsafat ilmu, untuk membangun dan mengembangkan suatu disiplin keilmuan tertentu, dibutuhkan setidaktidaknya 3 (tiga) landasan kefilsafatan yaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi. Ketiga landasan ini penting untuk membedakan secara jelas antara karaktristik jenis pengetahuan yang satu dengan jenis pengetahuan lainnya, termasuk antara jenis pengetahuan yang disebut dengan ilmu atau yang bukan ilmu. Ontologi adalah landasan yang menjelaskan tentang apa yang dikaji oleh pengetahuan itu, epistemologi menjelaskan tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan itu dan aksiologi memberikan penjelasan tentang apa kegunaan dari pengetahuan itu. Dengan mengenali jawaban dari ketiga landasan tersebut kita dapat membedakan berbagai jenis pengetahuan yang terdapat dalam kehidupan kita, seperti ilmu, filsafat, seni, dan agama serta meletakkannya pada tempatnya masing-masing secara tepat. Tanpa mengenali ciri-ciri ketiga landasan dari setiap pengetahuan itu secara tepat kita tidak dapat memanfaatkan kegunaanya secara maksimal, namun justru kita dapat salah dalam mempergunakannya. Ilmu Landasan Ontologi... 80 dikacaukan dengan seni, ilmu dikonfrontasikan dengan agama, filsafat dikonfrontasikan dengan seni, dsb.1 Landasan ontologis di sini dibutuhkan dan dimaksudkan untuk melihat bangunan tentang struktur ilmu dari aspek objek yang menjadi sasaran pemikiran atau kajian ilmu tersebut. Objek kajian ilmu dapat dibedakan menjadi objek kajian material dan formal. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa setiap disiplin ilmu pasti mempunyai objek kajian masing-masing baik terkait dengan objek material maupun objek formal. Objek material terkait dengan hakikat realitas yang dikaji atau diteliti atau sasaran pemikiran dari ilmu tersebut. Hal ini dapat mencakup realitas yang konkrit, seperti perilaku, benda-benda maupun yang abstrak seperti ide-ide dan nilai-nilai. Sementara itu objek formal terkait dengan sudat pandang orang melihat objek material dari realitas yang dikaji serta prinsip-prinsip yang digunakan. Objek formal ini dapat melahirkan berbagai pendekatan yang berbeda-beda sehingga melahirkan aliran-aliran dalam setiap disiplin keilmuan. Kedua objek kajian tersebut akan membingkai pada berbagai kajian dan penelitian dari displin ilmu tertentu. Dalam konteks perbincangan tentang landasan ontologi Ilmu Hukum Profetik kali ini pertanyaan mendasar yang muncul dan perlu dijelaskan adalah apa hakikat dari realitas yang disebut ‘hukum’ menurut perspektif paradigma profetik. Apa pengertianya, batasbatasnya, ciri-cirinya, unsur-unsurnya, dsb. Jawaban atas pertanyaan ini tentunya harus dimulai dengan mengemukakan asumsi atau anggapan dasar (basis assumption) apa yang dimaksud dengan hukum itu sendiri menurut pendekatan profetik. Asumsi atau anggapan dasar adalah pandangan-pandangan mengenai suatu realitas, dalam hal ini hukum, yang tidak dipertanyakan lagi kebenarannya atau sudah diterima kebenarannya. Pandangan ini merupakan titik-tolak atau dasar bagi upaya memahami dan menjawab suatu persoalan, karena Jujun S. Suriasumantri. 1994. Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hlm. 35. 1 Bab 3 81 pandangan-pandangan tersebut dianggap benar atau diyakini kebenarannya. Anggapan-anggapan ini bisa lahir dari (a) perenunganperenungan filosofis dan reflektif, bisa dari (b) penelitian-penelitian empiris yang canggih, bisa pula dari (c) pengamatan yang seksama.2 Asumsi dasar dibutuhkan agar kita mempunyai titik berdiri (standing point) pemikiran kita tentang hakikat hukum itu. Tanpa asumsi dasar kita akan kesulitan dan mungkin menjadi bingung memahami tentang hukum dan segala persoalan yang terkait dan berkelindan dengannya. Dalam tradisi keilmuan hukum yang umum, terdapat dua arus besar (mainstream) asumsi dasar atau anggapan dasar tentang realitas hukum itu, pertama pandangan dogmatik dan kedua pandangan empirik. Pandangan Dogmatik mengasumsikan atau menganggap bahwa hukum itu realitas kesejatiannya adalah norma. Norma adalah pedoman perilaku manusia dalam segala hal, yang eksistensinya berada di alam keharusan (sollen) yang dapat berujud nilai-nilai, gagasan-gagasan atau kehendak. Realitas hukum dalam pandangan normatif ini tidak berada di alam nyata (sein). Hal yang ada di alam nyata atau empirik hanyalah merupakan perwujudan atau penampakan saja dari hakikat hukum itu, dan itu bukan hukum yang sejatinya. Hukum yang sebenar-benarnya adalah apa yang berada di alam nilai-nilai atau alam kaidah yang bersifat metafisis. Hal yang ada di alam empirik atau alam nyata hanyalah sebatas manifestasi atau perwujudan dari hukum, yang fisiknya dapat berupa putusan-putusan, perjanjian-perjanjian, peraturan perundang-undangan, perilaku ajek yang mempola atau kebiasaan, dan simbol-simbol baik yang berujud fisik maupun budaya. Konsep normatif tersebut dijabarkan lebih lanjut oleh Wignjosoebroto menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu pertama, norma (hukum) yang dikonsepkan sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai Baca Heddy Shri Ahimsa-Putra. 2011. “Paradigma Profetik sebuah Konsepsi”, Makalah disampaikan dalam Diskusi Pengembangan Ilmu Profetik 2011,diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum - UII, di Yogyakarta, 18 Nopember 2011. 2 Landasan Ontologi... 82 universal, dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam, atau bahkan tak jarang dipercaya juga sebagai bagian dari kaidah-kaidah yang supranatural sifatnya. Kedua, norma (hukum) yang dikosepkan sebagai kaidah-kaidah positip yang berlaku umum in abstracto pada suatu waktu tertentu dan di suatu wilayah tertentu, dan terbit sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi, atau yang lebih dikenal sebagai hukum nasional atau hukum negara. Ketiga, norma (hukum) yang dikonsepkan sebagai keputusan-keputusan yang diciptakan hakim in concreto dalam proses-proses peradilan sebagai bagian dari upaya hakim menyelesaikan kasus atau perkara, yang berkemungkinan juga berlaku sebagai preseden untuk menyelesaikan perkara-perkara berikutnya.3 Sementara itu pandangan empirik mempunyai asumsi dasar bahwa realitas yang sebenar-benarnya dari hukum itu berada di alam nyata, empirik, yang bersifat riil dan konkrit. Wujud dari hukum tersebut dapat berupa perilaku ajek seperti kebiasaan, keteraturan, institusi hukum, aksi-interaksi masyarakat, ketertiban, ketaatan atau keasadaran hukum suatu masyarakat, dsb. Konsep empirik hukum tersebut dijabarkan lebih lanjut Soetandyo Wignjosoebroto (1994), menjadi sekurang-kurangnya dua konsep hukum, yaitu pertama, hukum dikonsepkan sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam sistem kehidupan bermasyarakat, baik dalam proses-proses pemulihan ketertiban dan penyelesaian sengketa maupun dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru. Kedua, hukum dikonsepkan sebagai makna-makna simbolik sebagaimana termanifestasikan dan tersimak dalam dan dari aksi-aksi serta interaksi warga masyarakat.4 Konsep yang pertama, di dalam literatur-literatur adalah konsepkonsep yang digolongkan sebagai konsep-konsep normatif. Konsep normatif ini memandang hukum sebagai norma entah norma yang Baca Soetandyo Wignjosoebroto. 2013. Hukum, Konsep dan Metode. Malang: Setara Press. Hlm. 18-34. 4 Ibid. 3 Bab 3 83 diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (ius constituendum) entah norma-norma yang nyata-nyata telah terwujud sebagai perintahperintah yang ekplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (ius costitutum) guna menjamin kepastiannya, entah pula norma-norma hasil cipta penuh pertimbangan hakim pengadilan (judgments) tatkala sang hakim ini mencoba menghukumi suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak berperkara. Karena setiap norma itu — entah yang berupa asas moral keadilan, entah yang telah dipositipkan sebagai hukum perundang-undangan, entah yang judge made —selalu eksis sebagai bagian dari suatu sistem doktrin atau ajaran (ialah ajaran tentang bagaimana hukum harus ditemukan atau dicipta untuk menyelesaikan perkara), maka setiap peneliti hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma ini dapatlah disebut sebagai peneliti normatif. Dalam tradisi Eropa Kontinental, menurut literatur-literatur berbahasa Belanda, kajian-kajian dan penelitian-penelitian hukum dalam konsepnya yang normatif ini disebut kajian atau penelitian dogmatik. Di dalam literatur-literatur berbahasa Inggris, khususnya karena pengaruh penulis-penulis Amerika Serikat yang melihat hukum sebagai doktrin yang luwes di tengah suatu realita proses, kajian-kajian dan penelitian-penelitian normatif itu lebih lazim disebut kajian-kajian atau penelitian-penelitian dengan metode doktrinal.5 Kajian-kajian yang dogmatik atau doktrinal ini lazimnya bermula dari upaya-upaya untuk membangun sistem hukum yang normatifpositivistik sebagai suatu model yang sempurna menurut imperativaimperativa logika. Koleksi atau inventarisasi untuk mengkompilasi bahan-bahan hukum akan segera dikerjakan, untuk kemudian menyususnnya ke dalam suatu tatanan normatif yang koheren (tidak mengandung kontradiksi-kontradiksi antar norma di dalamnya), namun yang juga memudahkan penelusurannya kembali. Bahan-bahan hukum 5 Ibid. Landasan Ontologi... 84 positif ini disebut bahan-bahan primer dan akan dimanfaatkan sebagai sumber hukum yang formil, disusun berdasarkan asas-asas dogamtik yang bermaksud menghindarkan terjadinya kontradiksi antar norma, seperti misalnya asas lex posteriori deragat lex priori atau asas yang diperkenalkan sebagai stuffenteorie oleh Kelsen. Untuk menjaga koherensinya itu, konfiguarsi-konfigurasi teoretik juga dikembangkan lewat berbagai bahasan atau ulasan dan komentar-komentar tertulis yang kemudian juga diiventarisasikan ke dalam suatu koleksi yang disebut koleksi bahan-bahan sekunder yang nantinya juga akan dapat difungsikan sebagai sumber hukum yang materiil.6 Sementara itu, konsep yang kedua yakni konsep hukum yang empirik adalah konsep-konsep yang bukan normatif, melainkan sesuatu yang nomologik. Di sini hukum bukan terkonsepsikan sebagai rules, melainkan sebagai regularities yang terjadi di alam pengalaman dan sebagaimana yang tersimak di alam kehidupan sehari-hari, sine era et studio. Di sini hukum adalah perilaku-perilaku (atau aksi-aksi dan interaksi) manusia yang secara aktual telah dan/atau yang secara potensial akan terpola. Karena setiap perilaku atau aksi itu adalah suatu realita sosial yang tersimak di alam pengalaman inderawi yang empirik, maka setiap penelitian yang mengkonsepsikan hukum sebagai perilaku dan aksi ini dapatlah disebut sebagai penelitian sosial (tentang hukum), penelitian empirik, atau penelitian yang non-doktrinal. Kajian-kajian tipe ini adalah kajian-kajian keilmuan, dengan maksud hendak mempelajari dan bukan hendak mengajarkan sesuatu doktrin untuk menemukan dan menegakkan hukum. Oleh sebab itu, metode yang lazim dipakai dalam kajian-kajian ini, di dalam literatur-literatur internasional berbahasa Inggris selama ini, lazim sekali disebut metode non-doktrinal, yang pada dasarnya adalah juga metode ilmu-ilmu sosial.7 Pembedaan ke dalam dua kategori besar metode penelitian hukum yaitu doktrinal dan non-doktrinal itu bersejajar pula pada pembedaan logika 6 7 Ibid Ibid. Bab 3 85 yang mendasari penelitian-penelitian hukum tersebut. Pada penelitian hukum yang doktrinal, logika formil dengan silogisme deduktif itulah lazim banyak dipakai. Hal itu mudah dimengerti karena memang hanya lewat deduksi itu orang akan dapat menemukan premis-premis dasar yang akan melandasi kebenaran suatu kaidah hukum in concreto, sedangkan kita mengetahui bahwa dalam penelitian-penelitian doktrinal itu para pencari “apa hukum untuk suatu perkara” memang bermisi mencari dan menemukan dasar legitimasi suatu kaidah atau suatu putusan hukum.8 Sementara itu pada penelitian-peneltian hukum yang non-doktrinal, logika materiil dengan silogisme induktif itu yang lazim akan banyak dipakai. Hal itu mudah pula dimengerti bahwa dalam penelitian nondoktrinal yang hendak dicari bukanlah dasar-dasar pembenaran berlakunya suatu kaidah atau keputusan, melainkan pola-pola keajekan atau pola-pola hubungan, entah yang korelasi atau kausal, antara berbagai gejala yang memanifestasikan hadirnya hukum di alam kenyataan yang bisa disimak oleh indera pengamatan.9 B. Pengaruh Paradigma Positivisme pada Ontologi Ilmu Hukum Pada pertengahan abad ke-19 di Eropa Kontinental, khususnya di Perancis berkembang filsafat baru yang disebut Filsafat Postivisme. Filsafat ini diajarkan oleh dua eksponen yang terkenal yaitu Henri SaintSimon (1760-1825) dan Auguste Comte (1798-1857). Di Inggris filsafat jenis ini dikembangkan oleh Herbert Spencer. Positivisme adalah suatu paham yang menuntut agar setiap metodologi yang dipikirkan untuk menemukan kebenaran hendaklah memperlakukan realitas sebagai sesuatu yang eksis, sebagai suatu objek, yang harus dilepaskan dari sembarang macam pra-konsepsi metafisis yang subjektif sifatnya.10 Ibid. Ibid. 10 Gardon, Scott. 1991. The History and Philosophy of Social Science. London: Toutdge. P. 301. 8 9 Landasan Ontologi... 86 Menurut Auguste Comte, apa yang sosial atau masyarakat dapat diredusir ke dalam dalil-dalil yang pasti dan ilmiah. Comte membuat suatu klasifikasi ilmu pengetahuan yang terus-menerus mengarah pada kesederhanaan dan generalitas dari masalah-masalah dalam subjeknya (subject matter) yaitu mathematics, astronomi, physika, kimia, biologi, dan sosiologi. Setiap cabang ilmu yang lahir harus bersandar pada hasil cabang ilmu sebelumnya, sehingga dalam pandangannya Sosiologi adalah puncak dari segala ilmu tersebut. Semua cabang ilmu tersebut hanya mempunyai dasar untuk adanya bilamana masing-masing cabang ilmu tersebut dapat memberikan bahan-bahan penjelasan lebih lanjut kepada ilmu mengenai kemasyarakatan. Dalam pandangan Comte setiap cabang ilmu itu merupakan suatu yang sudah exact, sudah pasti; dan dalam hal itu pengetahuan tersebut permasalahannya menjabarkan diri dari satu lingkungan masalah ke masalah lainnya dalam urutan sebagaimana diajukan olehnya. Dalam kerangka itu maka bagi Comte wajar bilamana komplek phenomena dari kehidupan masyarakat adalah yang paling akhir untuk digarap secara ilmiah.11 Bagi Comte setiap cabang ilmu tersebut pada masa-masa yang silam digarap melalui tiga tahapan yaitu: tahap teologis, tahap metafisis, dan tahap positivis. Pada tahap teologis ditunjukkan oleh kenyataan bahwa segala kejadian di dalam cabang ilmu pengetahuan yang bersangkutan diselesaikan dengan mengemukakan bahwa itu merupakan kehendak tuhan. Dalam tahap metafisis penyelesaian dicari dengan jalan abstraksi metafisis, misalnya kenyataan bahwa bintangbintang bergerak dalam lingkaran, dijelaskan karena lingkaran adalah suatu gerak yang paling sempurna. Pada tahap positivis dibuktikan bahwa setiap permasalahan diusahakan penyelesainnya secara ilmiah positip yaitu melalui suatu pengamatan yang cermat atas kejadiankejadian, membuat hipotesis dan verivikasinya melalui eksperimenM. Koesnoe. 1981. “Kritik Terhadap Ilmu Hukum”. Makalah Ceramah di Hadapan Para Dosen dan Mahsaiswa Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 3-4 Pebruari 1981. Hlm. 3-4. 11 Bab 3 87 eksperimen, kemudian menjelaskannya dengan jalan keajegan-keajegan yang tunduk pada hukum sebab-akibat (kausalitas).12 Pemikiran filsafat positivisme ini pada akhirnya berimbas pula pada dunia studi di dalam Ilmu Hukum, terutama pada anggapan dan pendekatan bahwa Ilmu Hukum juga harus merupakan suatu ilmu yang positip, seperti yang dimaksud oleh Comte. Artinya bahwa perihal hukum sebagai masalah kemasyarakatan manusia harus pula diselesaikan dengan pengamatan kejadian masyarakat secara cermat, kemudian disusun hipotesa dan mengadakan verifikasi melalui eksperimen-eksperimen serta dari itu baru pada kesimpulan yang menjelaskn dengan pasti menurut hukum sebab akibat. Dunia Ilmu Hukum adalah suatu ilmu yang dalam kaitan dengan tata ilmu sebagimana dimaksud oleh Comte di atas tidak dapat masuk dalam tatanan tersebut. Diaplikasikannya ke dalam pemikiran tentang hukum, positivisme juga menghendaki dilepaskannya pemikiran meta-yuridis mengenai hukum sebagimana dianut oleh para eksponen aliran hukum kodrat. Karena itu setiap norma hukum haruslah eksis dalam alamnya yang obyektif sebagai norma-norma yang positip, ditegaskan sebagai wujud kesepakatan kontraktual yang konkrit antara warga masyrakat (atau wakil-wakilnya). Hukum tidak lagi dikonsepsi sebagai asas-asas moral meta-yuridis yang niskala (abstrak) tentang hakikat keadilan, melainkan ius yang telah mengalami positivisasi sebagai lege atau lex, guna menjamin kepastian mengenai ‘apa yang terbilang hukum’ dan ‘apa pula yang sekalipun normatif harus dinyatakan sebagai hal-hal yang bukan terbilang hukum’.13 Paham positivisme dan pengaruhnya dalam kehidupan bernegara, segera mengupayakan positivisasi norma-norma sosial (yang ius) menjadi norma perundang-undangan (menjadi lege). Positivisasi hukum Ibid. Soetandyo Wignjosoebroto, 2002. Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. Jakarta: Huma. Hlm. 96. 12 13 Landasan Ontologi... 88 menjadi prioritas utama dalam setiap pembangunan hukum di negaranegara yang tengah tumbuh modern dan menghendaki kesatuan dan atau penyatuan. Positivisasi hukum juga selalu berakibat sebagai proses nasionalisasi hukum dalam rangka penyempurnaan kemampuan negara dan pemerintah untuk memonopoli kontrak sosial yang formal melalui pemberlakuan atau pendayagunaan hukum positip.14 Proses positivisasi pada hakikatnya adalah suatu proses obyektivikasi sejumlah norma meta-yuridis menjadi sejumlah norma yang positip. Prosesnya tetap saja berlangsung dalam ranah normatif, sehingga Ilmu Hukum yang terbangun adalah tetap berdasarkan logika normologi yang deduktif, bukan berdasarkan logika nomologi yang induktif, untuk menemukan berbagai nomos yang eksis sebagai fenomena empiris dalam kehidupan sosial dan kultural. Hubungan kausal antara sebab (fakta hukum) dan akibat (akibat hukum) dalam ilmu hukum yang berparadigma positivisme adalah hasil normatif judgement, bukan hasil observasiobservasi yang mendayagunakan metode sains guna menjamin obyektivitas dan reliabilitas.15 Kritik terhadap paradigma positivisme dalam Ilmu Hukum ini bermula dari suatu pemikiran kritis yang mencoba mempertanyakan pengertian ‘fenomena positip ‘ dalam paham positivisme itu sendiri. Kritik ini muncul bukan dari kalangan filsafat hukum, akan tetapi dari kalangan ilmuwan dan pemikir filsafat ilmu serta para matematisi sekitar tahun 1920-an yang menamakan diri ‘Kelompok Wina’ (The Viena Circle). Hasil kerja kelompok ini yang mendekonstruksi positivisme sebagai paradigma keilmuan, kemudian secara langsung atau tidak langsung turut berpengaruh pada perubahan pendekatan paradigma positivisme dalam Ilmu Hukum. Kelompok Wina ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan The Logical Positivism. Kelompok ini menyatakan bahwa metode ilmu-ilmu alam kodrat adalah satu-satunya sumber yang rasional untuk Luhman, Niklas. 1985. A Sociological Theory of Law. London: Routledge & Kegan Paul. P. 103; 15 Gardon Scott. Op.Cit. 33 14 Bab 3 89 memperoleh pengetahuan yang universal. Oleh karena itu metode ini harus dipakai dalam setiap kerja penelitian, termasuk penelitian sosial. Setiap pernyataan yang dianggap memiliki kebenaran harus ditentukan oleh bukti-bukti yang empiris dan setiap penelitian itu harus benarbenar obyektif dengan mewajibkan si peneliti untuk mengontrol keberpihakannya yang subyektif dengan berkomitmen pada nilai-nilai kenetralan asasi.16 Untuk mencari kebenaran ilmiah, ilmuwan tidak boleh melibatkan emosi dan keberpihakan apapun dan tugasnya hanyalah membuat studi. Sine era et studio.17 Jika diproyeksikan ke dalam pemikiran filsafat dan Ilmu Hukum, di sini orang tidak lagi hanya memahami hukum secara epistemologi sebagai produk positivisme yang bertolak dari keputusan politik rezimrezim yang berkuasa atau negara, melainkan orang mulai memahami hukum sebagai fakta sosial, yaitu law as what is empirically observed in society. Ilmu Hukum pun mendapatkan pendefinisian yang lebih luas, tak lagi sebatas reine Rechtslehre atau positive Jurisprudence yang Kelsenian, melainkan juga sebagai socio-legal studies, dengan menempatkan hukum sebagai fenomena empiris sebagai obyek kajian. Metodologi yang digunakan bertumpu pada paradigma epistemologis the logical positivism yang dirintis oleh Kelompok Wina.18 C. Pengaruh Paradigma Postpositivisme pada Ontologi Ilmu Hukum Kritik terhadap paradigma positivisme dalam kajian-kajian sosial dan humaniora dan kemudian juga pada kajian hukum, terutama pada kajian the legal studies dan bukan pada positive jurisprudence, bertolak dari suatu premis bahwa fakta sosial itu pada hakikatnya adalah sejumlah realitas yang terwujud sepanjang berlangsungnya interaksi-interaksi 16 17 18 Martyn Hammersley.1995. The Politics of Social Research. London: Sage. p. 2-7. Soetandyo Wignjosoebroto. Op.Cit. 98. Black, Donald. 1976. The Behavior of Law. New York: Pegassus. P. 19. Landasan Ontologi... 90 antara manusia di dalam kehidupan sosialnya. Dengan kata lain fakta sosial itu bukanlah suatu yang objektif dan eksis ‘di luar sana’ melainkan suatu konstruksi yang berada di dalam ranah subjektivitas manusia yang tengah berinteraksi. Maka tidak akan ada suatu realitas sosial yang berlaku universal, sehingga tidak akan ada pula fakta atau konstruksi realitas sosial yang dapat diverivikasi validitasnya melalui metodemetode yang berparadigma positivisme. Penganut paham tersebut oleh Collin (1997) disebut kaum Social Constructivist. Kelompok ini berupaya mendefinisikan ulang apa yang disebut realitas sosial. Kelompok social constructivist ini mempunyai variasi argumentasi dalam mendefinisikan realitas sosial. Collin (1997) mendiskripsikan setidak-tidaknya terdapat 8 (delapan) posisi argumentasi yaitu: etnometodologi, relativisme budaya, konstruktivisme sosial Bergerian, relativisme linguistic, fenomenologi, simbolisme fakta sosial, paradigma konvensi, dan hermeneutic.19 Aplikasi paradigma konstruktivisme sosial di bidang kajian hukum pada umumnya dilakukan dengan bertitik tolak dari posisi Hermeneutik. Kajian sosial dan hukum yang bertolak dari pendekatan hermeneutik ini secara tegas menolak faham universalisme dalam ilmu, khususnya ilmu yang objeknya manusia dan masyarakatnya. Sebagai gantinya relativisme itu yang harus diakui dan diterima. Pendekatan hermeneutik adalah pendekatan untuk memahami objek (produk perilaku manusia yang berinteraksi atau berkomunikasi dengan sesamanya), dari sudut pelaku pelaku aksi-interaksi (aktor) itu sendiri, artinya tatkala mereka itu tengah terlibat atau melibatkan diri di/ke dalam suatu proses sosial, termasuk juga proses-proses sosial yang relevan dengan permasalahan hukum. Pendekatan hermeneutik berasumsi secara paradigmatik bahwasanya setiap bentuk dan produk perilaku antar manusia itu akan selalu ditentukan oleh interpretasi yang dibuat dan disepakati para pelaku yang tengah terlibat dalam proses itu, yang tentu saja akan Soetandyo Wignjosoebroto. 2000. “Permasalahan Paradigma dalam Ilmu Hukum”. Jurnal Ilmu Sosial Transformatif , Edisi 6- Tahun II 2000. Hlm. 18. 19 Bab 3 91 memberikan keragaman maknawi pada fakta yang sedang dikaji sebagai objek.20 Pendekatan hermeneutik (interpretatif) dalam kajian hukum ini tidak hanya akan membebaskan kajian-kajian hukum yang otoritarianisme para yuris positivis yang elit, akan tetapi juga dari kajian-kajian hukum kaum strukturalis atau behavioralis yang terlalu empiris sifatnya. Pendekatan ini dengan strategi metodologiknya to learn from the people mengajak para pengakaji hukum agar juga menggali dan meneliti makna-makna hukum dari perspektif pengguna dan / atau pencari keadilan sebagaimana dikatakan oleh Sarat (1992) ‘...as an alternative, or addition, to (the study of legal) behavior’. Kajian hukum tipe ini tidak bermaksud menggantikan sepenuhnya pendekatan-pendekatan lain. Pendekatan ini tidak hendak mengklaim diri sebagai satu-satunya pendekatan yang sah dalam kajian-kajian sosial dan hukum, sebagaimana halnya pendekatan positivis, yang tidak sekali-kali pernah dapat mengklaim paradigma dan metode serta teknik penelitiannya sebagai satu-satunya yang sah untuk mempelajari hukum. Benar apa yang dikatakan Sarat (1992) tersebut, bahwa pendekatan baru ini hanyalah merupakan alternatif yang akan menambah kekayaan khasanah kajiankajian tentang hukum.21 D. Posisi Ilmu Hukum di Tengah Perkembangan berbagai Paradigma Utuk membahas posisi Ilmu Hukum di tengah berbagai paradigma yang ada, penulis menggunakan pendekatan pemikiran Neo-Kantian. Paradigma pemikiran Neo-Kantin membedakan secara tajam antara dua macam alam di dalam kesemestaan yaitu adanya alam ‘sein’ yaitu alam wujud secara fisik atau pengalaman dan alam ‘sollen’ yaitu alam abstrak yang tidak berada dalam dunia fisik atau pengalaman. Terkait dengan 20 21 Ibid. Hlm. 19. Ibid. 92 Landasan Ontologi... persoalan Ilmu Hukum, maka kalangan ini menyatakan bahwa ilmu pengetahuan hukum adalah termasuk dalam lingkungan ilmu pengetahuan kejiwaan atau kebudayaan. Bilamana diperhatikan sifat keilmiahan dari ilmu hukum, maka perlu dibedakan antara kedua macam alam tersebut yaitu alam ‘sein’ dan alam ‘sollen’. Ada Ilmu Hukum yang mempelajari alam sein dan Ilmu Hukum yang mempelajari alam sollen. Terhadap ilmu pengetahuan hukum yang mempelajari alam ‘sein’ dari hukum, maka ilmu pengetahuan hukum tipe ini yang dianggap benar-benar ilmiah sebagaimana konsep ilmu kaum positivism. Ilmu pengetahuan hukum yang mempelajari alam sein ini dapat digolongkan kepada ilmu tentang fakta-fakta (hukum) atau yang disebut sebagai ‘Tatsachenwissenchaft’ yang termasuk sebagai cabang Ilmu Sosiologi. Ilmu Hukum ini adalah cabang sosiologi yang disebut Rechtssociologie. Terhadap alam sollen dalam lingkungan Ilmu Hukum, juga ada yang mempelajarinya. Akan tetapi terhadap alam ini perlu dibedakan terlebih dahulu ilmu pengetahuan hukum yang mempelajari hubungan yang logis dari gejala-gelalanya saja tanpa melihat pada isinya, dan ilmu pengetahuan hukum yang berusaha menjelaskan bagaimana isi dan maksud yang sesungguhnya dari kaidah-kaidah hukum itu. Ilmu pengetahuan yang pertama disebut sebagai ajaran hukum formal (Formale Rechtlehre) karena hanya membicarakan hubungan-hubungan yang logis saja dari gejala-gejala hukum yang ada, yaitu dari segi formalnya saja. Sementara itu ilmu pengetahuan hukum yang mengenai isi dan maksud dari kaidah-kaidah hukum itu tidak dapat diterima oleh kalangan Neo-kantian sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan hukum ini tidak mempunyai tempat di dalam lingkungan ilmu pengetahuan dalam arti positip di atas. Terhadap objek yang disebut hukum, pemikiran yang bersandar pada paradigma Neo-Kantian mendapatkan suatu tempat yang penting dalam sejarah peningkatan Ilmu Hukum. Pembedaan antara alam ‘sein’ dan ‘sollen’ menjadi dasar untuk membenarkan keilmiahan dari Ilmu Bab 3 93 Hukum yang mengenai kaidah-kaidahnya, membantu dengan kuat tempat dan kedudukan Ilmu Hukum sebagai ilmu. M. Keosnoe memberikan catatan tentang Ilmu Hukum yang berobjek alam sollen dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Alam sollen adalah suatu alam yang tidak berujud dalam arti dapat ditangkap oleh pancaindera. Alam ini adalah abstrak yang hidup dan berada di alam jiwa manusia sebagai bagian dari alam yang berkehendak. Berkehendak artinya suatu kegiatan jiwa yang hidup yang berusaha untuk menjadikan apa yang ada dalam alam cita-cita menjadi alam kenyataan. Dengan demikian alam kehendak tidak sama dengan alam kenyataan. Alam kehendak mempunyai keadaannya yang lain dari alam kenyataan. Alam kehendak tidak dapat didekati dengan mempergunakan eksperimen-eksperimen yang diobservir dengan cermat kemudian diolah berdasar suatu pemikiran yang logis sehingga akhirnya dapat ditemukan dalil-dalil umum yang pasti. Alam kehendak tidak dapat dikdekati dengan jalan pemikiran kausal (sebab-akibat).22 Alam hukum menurut Koesnoe berada dalam alam sollen ini. Alam hukum tidak berada dalam tatanan empiris yang dapat ditangkap dengan pancaindera. Hukum dalam alam sollen mempunyai isi yang sifatnya normatif dan juga imperatif. Normatif artinya memerintah untuk melaksanakan isi kehendak, sedangkan imperatif artinya menuntut untuk ditaati kehendak yang bersangkutan dengan setepat-tepatnya. Alam hukum sebagai suatu alam kehendak yang normatif dan imperatif bilamana diselesaikan secara ilmiah, menuntut pula syarat-syarat kepastian sebagaimana setiap hasil ilmu pengetahuan yaitu melalui pembuktian-pembuktian yang tidak dapat diragukan. Kehendakkehendak sebagaimana ada dalam hukum perlu dibuktikan secara pasti dengan menggunakan alat-alat bukti. Dalam lingkungan ilmu hukum pengertian bukti mempunyai syarat-syarat dan tuntutan-tuntutan yang lain daripada apa yang ada dalam lingkungan ilmu pengetahuan alam. Apa yang mungkin dibuktikan dalam lingkungan ilmu pengetahuan alam, seperti tes mengenai darah misalnya, belum tentu dapat diterima 22 M. Koesnoe. 1981. Op.Cit. Hlm. 10. Landasan Ontologi... 94 oleh hukum sebagai bukti yang meyakinkan. Misal dalam hal seorang anak memerlukan pembuktian tentang benar tidaknya anak tersebut sebagai anak kandung dari seorang bapak, dapat terjadi bahwa tes darah dapat menjawab adanya kesamaan darah anak dengan laki-laki yang dianggap bapaknya. Akan tetapi bagi hukum belum tentu diterima secara sah, karena ada kemungkinan saksi-saksi lain serta bukti-bukti dalam bentuk dokumen yang oleh hukum dianggap lebih kuat dapat menyangkal pembuktian hasil ilmu pengetahuan alam dalam tes darah tersebut.23 Senada dengan pemikiran Neo-Kantian, yang membedakan adanya alam sein dan sollen, yang melahirkan ilmu pengetahuan hukum tentang fakta-faka (hukum) atau Tatsachenwissenchaft’ dan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kaidah (hukum), Mauwissen (1994) mengemukakan bahwa dapat dibedakan berbagai jenis Ilmu Hukum, yang meliputi Ilmu Hukum Dogmatik, Ilmu Hukum Empiris dan bentuk-bentuk lain seperti: Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum, Perbandingan Hukum, dan Psikologi Hukum.24 Ilmu Hukum Dogmatik bertugas untuk memaparkan, menganalisis, mensistematisasi dan menginterpretasi hukum yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memungkinkan penerapan dan pelaksanaan hukum secara bertanggungjawab di dalam praktik. Bentuk Ilmu Hukum ini menempati posisi sentral dalam pendidikan hukum di universites. Sementara Ilmu Hukum Empiris membedakan secara tajam antara fakta-fakta dan norma-norma, antara keputusan-keputusan (proposisi) yang memaparkan (deskripsi) dan yang normatif (preskriptif). Gejala-gejala hukum dipandang sebagai gejala empiris (faktual) yang murni, yaitu fakta-fakta kemasyarakatan yang dapat diamati secara inderawi. Gejalagejala ini harus dipelajari dan diteliti dengan menggunakan metodemetode empiris, sesuai dengan ‘gambaran standar’. Ini berarti bahwa Loc.Cit Mauwissen. 1994. “Ilmu Hukum”. Jurnal Pro Justitia. Tahun XII. Nomor 4 Oktober 1994. Hlm. 20-30. 23 24 Bab 3 95 hukum yang berlaku itu dipaparkan, dianalisis dan juga dijelaskan. Ilmu ini berbicara dalam keputusan-keputusan deskriptif tentang gejala-gejala hukum, yang untuk sebagian juga tampil dalam keputusan-keputusan preskriptif. Penelitian empiris faktual terhadap isi dari hukum, antara lain terhadap perilaku mereka yang terlibat dengan hukum. Ilmu Hukum ini bersifat bebas nilai dan netral. Pengembannya sama sekali tidak mengambil sikap (pendirian) menilai atau kritis terhadap gejala-gejala hukum yang ia pelajari dan jelaskan.25 Lebih lanjut Mauwissen (1994) mengemukakan bahwa terkait dengan pengembanan hukum dapat dibedakan ke dalam pengembanan hukum praktis dan pengembanan hukum teoritis. Pengembanan hukum praktis adalah kegiatan yang berkenaan dengan hal mewujudkan hukum dalam kenyataan kehidupan sehari-hari secara konkrit, yang meliputi kegiatan pembentukan hukum, penemuan hukum, dan bantuan hukum. Sementara itu pengembanan hukum teoritis atau refleksi teoritis adalah kegiatan akal budi untuk memperoleh penguasaan intelektual tentang hukum atau pemahaman tentang hukum secara ilmiah yakni secara metodis sistemtis-logis rasional. Berdasarkan tataran analisisnya (level of analysis) atau berdasarkan tingkat abstraksinya, pengembanan hukum teoritis dibedakan dalam tiga jenis. Pada tataran ilmu-ilmu positip, yang paling rendah tingkat abstraksinya, disebut ilmu-ilmu hukum. Pada tataran yang lebih abstrak disebut Teori Hukum, dan pada tataran filsafat yang abstraksinya paling tinggi disebut Filsafat Hukum yang meresapi semua bentuk pengemban hukum teoritis dan praktis.26 E. Ontologi Hukum sebagai Wilayah Terbuka Sebagaimana telah diuraikan di atas diketahui bahwa hukum sebagai objek kajian dapat dikaji dari berbagai pendekatan. Berbagai pendekatan yang digunakan tersebut membawa konsekuensi pada Ibid. Uraian panjang lebar tentang pengembanan hukum, baca Mauwissen. 1994. “Pengembanan Hukum “ PRO JUSTITIA Tahun XII Nomor 1 Januari 1994. Hlm. 61-81. 25 26 Landasan Ontologi... 96 tipologi kajian hukum yang berbeda-beda. Ada yang bercorak dogmatis, ada pula yang bercorak empiris. Ada yang bercorak teoretis, ada pula yang bercorak praktis. Semua jenis kajian tersebut adalah absah dan tidak perlu dipertentangkan. Dengan demikian, maka dalam berilmu hukum pun perlu diterima pendekatan yang bersifat holistik, yaitu pendekatan yang mengintegrasikan berbagai pendekatan yang ada untuk memahami lebih luas terhadap objek hukum sehingga didapatkan kebenaran hukum yang komprehensif. Pentingnya pendekatan holistik dalam kajian hukum ini dapat bersifat internal maupun eksternal. Sifat internal diperlukan untuk mengintegrasikan berbagai pendekatan yang ada yang sama-sama mengkaji hukum sebagai objek kajian. Sifat ekternal diperlukan untuk mengintegrasikan berbagai pendekatan di luar objek kajian ilmu hukum, yaitu terhadap disiplin ilmu-ilmu lain yang yang berobjek bukan hukum. Pendekatan holistik baik yang internal maupun ekternal ini dibutuhkan agar tercipta seperti apa yang dikatakan oleh Edward O. Wilson dalam Buku yang berjudul Consilience: The Unity of Knowledge. 27 Consilience merupakan gagasan utama yang ditawarkan Wilson dalam upaya membangun pandangan yang holistik dalam ilmu pengetahuan. Menurut Wilson consilience adalah suatu lompatan bersama dalam hal pengetahuan, dengan jalan mempertalikan dan mempersatukan fakta-fakta dan teori berdasarkan fakta di seluruh disiplin ilmu, guna menciptakan suatu dasar penalaran atau alasan yang sama untuk memberi penjelasan. Ilmu berada pada wilayah terbuka dan sebagai sistem jaringan yang terhubung satu sama lain dalam kerangka analisisnya. Wilson menolak pandangan klaim pemilahan analisis tentang ilmu yang selama ini ditawarkan sejak pemikiran Aristoteles, Newton dan Discartes. Ia mencoba membuka katub ilmu yang selama ini tertutup sehingga dimungkinkan terjadinya holisme ilmu pengetahuan.28 Bagi Ilmu Hukum pandangan Wilson di atas membenarkan Baca Edward O. Wilson. 1998. Consilience, The Unity of Knowledge. Alfreda Knoff New York. 28 Ibid. Hlm 266. 27 Bab 3 97 pandangan alternatif bagi pendekatan kajian hukum. Kalangan pengkaji hukum perlu menyadari bahwa selama ini ilmu hukum didominasi oleh pemikiran yang cenderung positivistik dan terpilah. Dominasi ini begitu kuatnya sehingga terkadang menyulitkan apabila ingin melakukan analisis yang bersifat lintas metodologi. Pandangan Wilson sangat bermanfaat untuk menjelaskan pendekatan holistik di dalam Ilmu Hukum. Ini dapat dijelaskan sebagai berikut ini. Perdebatan paling tajam dalam ranah epistemologi Ilmu Hukum adalah menjawab pertanyaan apakah hukum itu ilmu atau bukan seperti telah dikemukan di pokok permasalahan. Ada semacam problem filosofis di dalam perdebatan demikian, bahkan terkesan berbelit dan berputarputar seperti sebuah lingkaran. Consilience menawarkan sebuah alternatif pemikiran yaitu hukum menjadi sebuah model jaringan dan memilki kesatuan konseptual dengan disiplin lainnya, semacam keterikatan dalam sebuah jaringan laba-laba. Sebagai sebuah jaringan ilmu pengetahuan, maka ruang komunikasi akan terbuka sedemikian rupa, sehingga hukum dapat memecahkan problem bersifat lintas disiplin. Ini memberikan keleluasaan bagi pembentukan model analisis dalam hukum serta memberikan kemungkinan petualangan intelektual yang cukup luas tentang nilai kemanuasiaan untuk menjawab berbagai persoalan. Masing-masing ilmu mempunyai praktisi, metode, model analisis, serta standar kebenaran sendiri. Network (sistem jaringan) memberikan paling tidak suatu kesepakatan tentang kumpulan prinsip-prinsip abstrak dalam ilmu meski tidak menuju pada kesatuan kosnepertual, batasbatas wilayah ilmu menjadi semakin menghilang. Kalaulah batas itu ada, hukum tetap dapat masuk dan keluar denga bebas. Hukum dapat bekerjasama dengan disiplin lain untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Implikasinya akan sampai pada pemikiran bahwa hukum merupakan wilayah terbuka, bagi domain ilmu lain. Ini adalah model pendekatan yang oleh Barbour29 disebut dengan dialog antar ilmu, yaitu Ian G.Barbour. 2000. When Science Meets Religions; Enemies, Strangers, or Patner. Harper Collins Publisher Inc. Hlm 40-42. 29 Landasan Ontologi... 98 dialog ketika ilmu menyentuh persoalan di luar wilayah yang menjadi kajiannya, sehingga dapat ditunjukkan metode bidang-bidang ilmu baik kemiripan atau perbedaannya. Model dialog ini memotret hubungan lebih bersifat konstruktif, meski tidak menawarkan kesatuan konseptual. Model ini merupakan upaya ilmiah untuk mengeksplorasi kesejajaran metode antara ilmu (hukum ) dengan lainnya. Gagasan ini juga dapat disebut sebagai suatu proses komunikasi. Dialog menekankan kemiripan dalam pra-anggapan, metode dan konsep. Thomas Kuhn, menawarkan gagasan kesejajaran dalam apa yang disebut dengan paradigma, yaitu seperangkat pra anggapan konseptual, metafisik, dan metodologis dalam tradisi kerja ilmiah. Melalui paradigma baru data lama ditafsirkan ulang dan dipandang dengan cara baru, dan data baru dicoba ditemukan. Tidak ada aturan atau kriteria yang pasti untuk memilih satu diantara paradigma-paradigma yang ada. Paradigma merupakan penilaian yang dilakukan oleh komunitas ilmiah. Paradigma yang mapan ini cenderung resisten terhadap falsifikasi, dengan demikian ketidaksesuaian antara teori dan data dapat dianggap sebagai anomali atau didamaikan dengan memperkenalkan hipotesis ad hoc. Sebagai pandangan tentang hukum yang sosiologis, mencoba menalaah hubungan dialog ini antara anasisr-anasir hukum dengan nonhukum atau tertib hukum dengan tertib sosial30, hukum dengan kegiatan bisnis31 dan lain-lain. Inilah hakekatnya bahwa Ilmu Hukum merupakan sebuah jaringan. Secara teoretis dan praktis hukum sebagai sebuah disiplin hendaknya memiliki model analisis dan mampu menyelesaikan berbagai ragam persoalan. Satu hal yang dirasakan cukup menggangu adalah terlalu sempitnya lingkup batasan hukum yang dikemukan para teoretisi konvensional. Hukum digambarkan sebagai wilayah yang stiril dan Julius Stone. 1969. Law and Social Sciences. Minneapolis. University of Minnesota Press. Hlm 3-24. 31 Stewart Macaulay. 1963. Non Contractual Relation in Business. American Sociological Review. Hlm 55-67. 30 Bab 3 99 tertutup atau kedap air. Akibatnya tidak ada tempat bagi pandangan di luar klaim ini. Ini muncul karena kepercayaan yang sangat kuat bahwa hukum, adalah wilayah terkerangkeng dalam logika. Hukum mengalami kesulitan untuk melakukan terobosan analisis bahkan kesulitan untuk membentuk disain analisisnya sendiri. Singkatnya hukum tidak memiliki kemampuan melakukan sintesis ragam pendekatan. Analisis hanya berakhir pada pada apa yang disebut sebagai dominasi wilayah yang sempit, yaitu analisis yuridis yang meliputi aturan, kaidah dan sanksi atau paling jauh kekuatan analisis hukum pada nampak pada prosedur dan formalisme. Teori hukum, metodologi, pendidikan dan praktek hukum sangat didominasi oleh pandangan stiril dan tertutup. Analisis akan disebut analisis hukum jika analisis itu sangat logis (berada dalam logika sistem hukum) dan menggunakan term yang dikenal dalam keilmuan hukum. Hukum secara filosofis dan metodologis harus terpisah dari ilmu-ilmu lain. Dengan pendekatam holistik, wilayah hukum menjadi wilayah terbuka. Hukum menjadi domain telaah disiplin lain. Ragam pendekatan metodologis akan memperkaya serta memberikan terobosan baru dalam ranah keilmuan hukum. Model pendekatan holisitik ini menawarkan semacam integrasi menuju kepada kesatuan konseptual dalam ilmu pengetahuan. Dengan demikian gagasan-gagasan tentang hukum (khususnya pandangan konvensional /sempit dan steril) wajib mengalami perumusan ulang. Dengan mengikuti pendekatan holistik dalam Ilmu Hukum, maka menjadi tugas para ilmuwan untuk mengutuhkan kembali hukum, menyatukan kembali hukum dengan lingkungan alam, dan orde kehidupan yang lebih besar. Memasukkan studi hukum ke dalam orde yang lebih besar tersebut bertujuan untuk menghilangkan pemisahan antara hukum dan kehidupan manusia. Inilah yang dinamakan mengembalikan hukum ke dalam keutuhan. Metodologi demikian dapat dilakukan apabila setiap kali hukum membuat keputusan (legislasi, yudikasi ataupun enforcement) senantiasa melihat kepada keutuhan dengan kehidupan manusia. 100 Landasan Ontologi... Hukum tidak boleh mempertahankan eksistensinya sedemikian rupa sehinmgga menjadi suatu anomali dalam konteks keutuhan dengan kehidupan manusia.32 Melalui kejayaan dan dominasi paradigma positivisme-analitis sejak abad kesembilanbelas, sampai sekarang kita masih diwarisi oleh studi hukum yang menampilkan gambar hukum yang berkepingkeping (fragmented). Gambar hukum yang muncul dari studi itu bukan menampilkan sosok hukum yang utuh. Orang mempelajari Hukum Tatanegara, Hukum Pidana, Hukum Perdata dan seterusnya bukan dalam kesatuan keutuhan dengan lingkungannya, akan tepai terkepingkeping. Untuk menciptakan keutuhan, maka studi hukum harus dapat mengembalikan “darah, urat dan daging-daging hukum” melalui pendekatan holistik, yaitu memamparkan secara sosiologis, anthropologis, ekonomis, psikologis, dan seterusnya. Oleh karena itu perlu diasiapkan pengajar-pengajar Sosiologi hukum pidana, Anthropologi hukum tatanegara, Psikologi hukum Acara dan seterusnya. Paradigma holistik tersebut tentunya akan mengubah peta berhukum dan pembelajaran hukum yang selama ini memandu kita.33 F. Dimensi Ontologi dalam Ilmu Hukum Profetik Gagasan awal perlunya mengembangkan Ilmu-Ilmu Profetik ditebarkan oleh Kuntowijoyo pada sekitar tahun 2002. Gagasan ini diilhami oleh dua pemikir besar Muhammad Iqbal, dan Roger Garaudy, pemikir Perancis yang kemudian masuk Islam, sebagaimana telah dijelaskan pada uraian di bab1. Bagi Ilmu Hukum, munculnya Ilmu Profetik ini terasa mendapatkan gagasan baru yang patut diwadahi dan kemudian dikembangkan sebagai alternatif kajian keilmuan hukum, yang berbasis pada nilai-nilai profetik yang sumber utamanya adalah wahyu ilahi. Satjipto Rahardjo. 2005. “Pendekatan Holistik terhadap Hukum”. Jurnal Hukum Progresif Volume: 1 / Nomor 2/ Oktober 2005. Hlm 13; 33 Ibid. 32 Bab 3 101 Oleh karena itu, al-Qur’an dan al-Hadits dalam konteks Ilmu Hukum Profetik menjadi basis utama epistemologinya. Segala sesuatu yang ada dalam al-Quran dan Al-Hadits harus diketahui dan dipahami dengan baik terlebih dulu untuk dapat dijadikan landasan bagi keseluruhan bangunan Ilmu Hukum Profetik. Untuk itu, pengetahuan dan pemahaman tentang unsur-unsur yang relevan dari Al Quran dan alHadits akan sangat membantu pengembangan Ilmu Hukum Profetik. Di sini diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang baik dan benar mengenai kedua hal tersebut, di samping pengetahuan dan pemahaman mengenai Filsafat Ilmu, Filsafat Ilmu Hukum dan Filsadat Hukum pada umumnya. Dengan mendasarkan pada pengertian dan pemahaman seperti tersebut untuk sementara (tentatif) dapat dirumuskan bahwa Ilmu Hukum Profetik adalah Ilmu Hukum yang paradigmanya, asumsi-asumsi dasarnya, prinsip-prinsipnya, ajaran atau teorinya, metodologinya, struktur norma-normanya, dibangun berdasarkan basis epistemologi ajaran Islam yang bersumber pada al-Quran dan al-Hadits. Melalui proses transformasi dan objektivikasi ajaran Islam tentang hukum yang bersumber pada al-Quran dan al-Hadits tersebut (teks) dibangun asumsiasumsi dasar yang kemudian turun menjadi teori, doktrin, asas-asas, kaidah dan norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat sesuai dengan konteksnya masing-masing. Masyarakat yang dimaksud adalah baik masyarakat muslim maupun non-muslim. Tujuan transformasi dan objektivikasi tersebut didasarkan pada misi ajaran Islam sebagai rahmatan lil’alamin. Bangunan Ilmu Hukum Profetik didasarkan pada 3 (tiga) landasan etik profetik, yaitu humanisasi (amar makruf), liberasi (nahi munkar), dan transendensi (tukminuna billah), yang itu semua bertujuan untuk kesejahteraan umat manusia (baldatun thoyyibatun warobbun ghofur) secara sempurna (kaffah). Seperti halnya ilmu pada umumnya, Ilmu Profetik juga memiliki asumsi-asumsi dasar tertentu berkenaan dengan objek materialnya. Asumsi dasar ini sebagian dapat sama, sebagian dapat berbeda. Asumsi- 102 Landasan Ontologi... asumsi yang sejalan dengan asumsi Ilmu Hukum pada umumnya, dapat diambil untuk membangun Ilmu Hukum Profetik. Akan tetapi, mengambil dan menggunakan asumsi dasar dari paradigma-paradigma Ilmu Hukum pada umumnya tentunya tidak cukup, karena hal itu akan membuat Ilmu Hukum Profetik tidak ada bedanya dengan Ilmu Hukum pada umumnya. Jika kritik yang dilontarkan terhadap ilmu pada umumnya adalah sifatnya yang sekuler, maka kelemahan inilah yang tidak boleh terulang dalam Ilmu Hukum Profetik. Artinya, di sini harus dilakukan desekularisasi, yang berarti memasukkan kembali unsur sakral, unsur ke-Ilahi-an dalam ilmu (hukum) profetik. Bagaimana caranya? Menurut Ahimsa-Putra, salah satu caranya adalah dengan menempatkan kembali segala objek material Ilmu Profetik dan Ilmuwan Profetik dalam hubungan dengan Sang Maha Pencipta, Allah s.w.t. atau Tuhan Yang Maha Kuasa (dimensi transendensi). Di sini perlu diasumsikan bahwa meskipun alam dan kehidupan manusia adalah sebuah realitas yang ada, namun realitas ini tidak muncul dengan sendirinya. Realitas ini ada penciptanya. Oleh karena itu, kita tidak dapat memperlakukan realitas tersebut seenak kita, terutama seyogyanya kita tidak merusak realitas tersebut, kecuali kita memiliki alasan-alasan yang dapat diterima berdasarkan patokan etika dan estetika tertentu. Menempatkan kembali realitas objektif yang diteliti atau dipelajari sebagai ciptaan Allah Yang Maha Pencipta adalah apa yang oleh Kuntowijoyo disebut sebagai proses transendensi. Menurut Kuntowijoyo, “Bagi umat Islam sendiri tentu transendensi berarti beriman kepada Allah s.w.t. (tukminuna billah)”.34 Bagi Ilmu Hukum Profetik, kiranya perlu dipikir ulang apa sebenarnya yang menjadi objek material ilmu hukum profetik itu dan bedanya dengan Ilmu Hukum pada umumnya. Untuk mengetahui hal ini, maka yang perlu dipertanyakan adalah apa sebenarnya yang menjadi Kuntowijoyo. 2006. Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika. Yogyakarta: Tiara Wacana. Hlm.107. 34 Bab 3 103 hakikat dari hukum itu sendiri? Dalam Ilmu Hukum pada umumnya banyak asumsi dasar yang diikuti oleh para ilmuwan hukum untuk menjelaskan apa hakikat hukum itu. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto (1994), terdapat sekurangkurangnya lima asumsi dasar yang membentuk konsep hukum yang berbeda. Pertama, hukum dikonsepkan sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal, dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam, atau bahkan tak jarang dipercaya juga sebagai bagian dari kaidah-kaidah yang supranatural sifatnya. Kedua, hukum dikosepkan sebagai kaidah-kaidah positip yang berlaku umum in abstracto pada suatu waktu tertentu dan di suatu wilayah tertentu, dan terbit sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi, atau yang lebih dikenal sebagai hukum nasional atau hukum negara. Ketiga, hukum dikonsepkan sebagai keputusan-keputusan yang diciptakan hakim in concreto dalam proses-proses peradilan sebagai bagian dari upaya hakim menyelesaikan kasus atau perkara, yang berkemungkinan juga berlaku sebagai preseden untuk menyelesaikan perkara-perkara berikutnya. Keempat, hukum dikonsepkan sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam sistem kehidupan bermasyarakat, baik dalam proses-proses pemulihan ketertiban dan penyelesaian sengketa maupun dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru. Kelima, hukum dikonsepkan sebagai makna-makna simbolik sebagaimana termanifestasikan dan tersimak dalam dan dari aksi-aksi serta interaksi warga masyarakat.35 Berdasarkan pembagian konsep hukum seperti yang dikemukakan oleh Wignjosoebroto tersebut, dalam konteks Ilmu Hukum Profetik, asumsi dasar yang pertama (hukum sebagai asas-asas moralitas) nampaknya tidak jauh berbeda dan sejalan dengan asumsi dasar Ilmu Hukum Profetik. Hanya saja konsep tersebut perlu diberi isi yang lebih jelas terkait dengan ciri keprofetikannya. Menurut hemat penulis ciri Soetandyo Wignjosoebroto. 2002. Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. Jakarta: Huma. Hlm.42. 35 104 Landasan Ontologi... keprofetikan itu dapat ditunjukkan dengan asumsi dasar bahwa “hukum pada hakikatnya adalah kehendak Allah tentang sesuatu yang adil yang sumbernya terdapat pada al-Qur’an dan al-Hadits”. Untuk itu perlu dicari ayat-ayat dan hadits-hadits nabi yang berisi kehendak Allah tentang sesuatu yang adil tersebut sebagai basisnya. Sejalan dengan pengertian tersebut, Fakultas Hukum UII melalui Pola Ilmiah Pokok (PIP) telah merumuskan tentang esensi hukum sebagai berikut ini. Esesnsi hukum adalah kehendak, dan kehendak tertinggi yang kebenarannya bersifat hakiki adalah kehendak Allah SWT, yang diperuntukkan pada manusia, untuk dapat mencapai derajat yang mulia sebagai wakil Allah di muka bumi (Q.S.2:30). Karena itu sesungguhnya, hukum merupakan sarana dan wahana bagi manusia atas dasar keimanannya untuk mendapatkan ridho-Nya (Q.S. 2:147; 3:360; 18:29; 5:59). Dalam peringkat hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan ekosistemnya, hukum Allah harus menjadi landasan etik bagi hukum ciptaan manusia. Hukum ciptaan manusia pada dasarnya adalah perlanjutan yang konsisten dari hukum Allah (Q.S 5:44 dan 45; 4:59). Karena itu tegak dan eksisnya hukum-hukum ciptaan manusia dapat mendatangkan malapetaka bagi manusia dengan ekosistemnya, manakala tidak bersandarkan pada kehendak Allah (QS.30:41). Makna pendidikan adalah proses pemanusiaan manusia (humanisasi) dengan sarana ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sendiri pada dasarnya merupakan rahmat Allah SWT untuk manusia (QS.96:3-5). Dimensi rasionalitas ilmu pengetahuan bukan menjadi satu-satunya ukuran kebenarannya. Relativitas ilmu pengetahuan telah menunjukkan bahwa di dalam dirinya terkandung keserba mungkinan, yang senantiasa terikat ke ruang waktuan. Oleh karenanya, dalam pendidikan, ilmu pengetahuan yang bersumber pada ke-mahasegala-Nyalah yang mampu menghantarkan manusia kepada derajat yang mulia. Dan adalah suatu kebenaran, manakala pendidikan pada hakikatnya bertujuan menjadikan manusia semakin menyadari makna keberadaannya secara fungsional dan semakin mendorong manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT (QS. 3:73; 5:56; 58:11). Pendidikan hukum pada dasarnya adalah penggabungan secara kualitatif dan proporsional antara makna hukum dan makna pendidikan. Pendidikan hukum bukannya semata-mata membuat manusia menguasai ilmu hukum, tetapi lebih dari itu adalah membuat manusia mampu menfalsifikasi dan menferifikasi hukum-hukum yang ada atas dasar esensi hukum. Dengan kata lain hakikat pendidikan hukum adalah upaya menjadikan manusia agar dapat Bab 3 105 memahami hukum dan mengaktualisasaikannya untuk menegakkan keadilan dalam segala aspek kehidupan sebagai realisasi amanah Allah SWT (QS. 4:58; 5:2. Tujuan pendidikan nasional sebagaimana dirumuskan dalam GBHN tahun 1993 dan UU No.2 Tahun 1989, dengan tegas dan jelas menempatkan nilai-nilai kemanusiaan secara utuh, yakni membentuk manusia yang taqw kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan bertitik tolak dari rumusan tersebut maka pendidikan hukum harus mencerminkan upaya-upaya penjelmaan nilai-nilai yang terkandung dalam hakikat sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang subtansinya adalah nilai-nilai wahyu ilahi. Pasal 29 UUD 1945 mempertegas eksistensi nilai-nilai wahyu ilahi itu sebagai sumber nilai-nilai hukum di Indonesia. Dalam arti maknawi, Pasal 29 tersebut bukan hanya menjamin, tetapi sekaligus merupakan kerangka ideal bagi setiap lapisan/lembaga kemasyarakatan yang ada untuk bersama-sama menciptakan tatanan masyarakat dan bangsa yang bersifat religius. Dengan demikian pendidikan hukum yang berorientasi pada nilai-nilai wahyu ilahi dan nilai-nilai falsafati merupakan penjabaran Pancasila dan UUD 1945, dan sekaligus mencerminkan pola pendndikan hukum yang integratif dalam dimensi spiritual material dan dimensi kemnusiaan serta kemasyarakatan yang ber-Ketuhanan. Pola pendidikan hukum yang demikian akan mendekatkan pada kemampuan yang andal bagi pembentukan Sarjana Hukum yang berkepribadian, yang mencerminkan kepekaan dan sikap yang apresiatif terhadap realitas serta responsif terhadap tantangan kemajuan, sarjana hukum yang mampu beramal ilmiah dan berilmu amaliah demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur duniawi dan ukhrowi. Perguruan Tinggi sebagai pusat ilmu dan kebuadayaan merupakan lembaga yang terikat dan bertanggungjawab untuk terbentuknya tatanan masyarakat yang berbudaya, berkeadilan sosial dan berketuhanan, dalam konteks ini pendidikan hukum yang berpola pada identitas nilai-nilai yang bersumber dari agama, Pancasila dan UUD 1945 memerlukan perumusan Pola Ilmiah Pokoknya, yang berfungsi sebagai norma dasar akademik yang memberi arah terhadap seluruh aktifitas Fakultas Hukum UII. Pendidikan hukum di negara kita akan semakin bermakna manakala berdasar pada tujuan pendidikan nasional yang berorientasi pada Pancasila, dapat membuahkan sarjana hukum yang mampu berperan sebagai penegak hukum dan keadilan, yang bersumber adari agama, Pancasila dan UUD 1945 dirasakan sangat besar artinya. Oleh karena itu pendidikan sebagai perekayasaan manusia agar berwatak, bersikap dan berperilaku sejalan dengan tujuan penegakan hukum dan keadilan. Fakultas Hukum UII sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945 dan perpedoman pada ajaran Islam, mempunyai tugas luhur di dalam kerangka pencapaian tujuan 106 Landasan Ontologi... pendidikan hukum. Adalah merupakan fungsi yang dasariah sifatnya, bahwa dalam usianya yang semakin menua ini FH UII perlu merekonstruksi segala aktifitasnya agar kehadiranya dalam rangka aktualisasi tujuan UII menjadi lebih bermakna. Berdasarkan identitas, tujuan pendidikan, pasaran kerja dan kebutuhan masyarakat, program pendidikan tinggi FH UII menetapkan tema “PENEGAKAN HUKUM YANG BERWAWASAN QURANI” sebagai Pola Ilmiah Pokoknya. Pola Ilmiah Pokok tersebut berfungsi sebagai norma dasar akademis yang memberi arah seluruh aktifitas di FH UII yang dinyatakan di dalam keseluruhan kurikulum, silabus dan kegiatan akademik penunjangnya.36 Subtansi PIP yang dirumuskan oleh FH UII tersebut jika dicermati secara seksama merupakan jabaran tentang esensi hukum sebagaimana dikehendaki oleh Ilmu Hukum Profetik. Hukum pada hakikatnya adalah kehendak Allah yang ditujukan kepada manusia untuk mencapai derajat manusia yang mulia sebagai khalifah. Hukum berfungsi sebagai sarana dan wahana manusia untuk mendapatkan ridho-Nya. Nilai-nilai yang terumuskan dalam PIP tersebut sejalan dengan etika profetik yaitu humanisasi, leberasi dan transendensi. Dari uraian di atas dapat ditegaskan kembali beberapa hal yaitu bahwa basis utama dari Ilmu Hukum Profetik adalah Ajaran Islam yang terkandung dalam al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Oleh karena itu segala sesuatu yang ada dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah harus diketahui dan dipahami dengan baik dan benar terlebih dulu, untuk dapat dijadikan landasan bagi keseluruhan bangunan Ilmu Profetik. Tentu saja tidak semua unsur dalam al-Quran dan Sunnah Rasul relevan dengan pengembangan Ilmu Hukum Profetik. Untuk itu, pengetahuan dan pemahaman tentang unsur-unsur yang relevan akan sangat membantu dalam pengembangan Ilmu Hukum Profetik. Di sini diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang baik dan benar mengenai al-Quran dan Sunnah Rasul serta pengetahuan dan pemahaman mengenai Filsafat Ilmu pada umumnya dan Filsafat Ilmu Hukum. 36 Panduan Akademik 1997/1998. Fakultas Hukum UII. Hlm.21-24. Bab 3 107 Dari basis utama Alquran dan Sunnah Rasul, diturunkan lagi menjadi asumsi-asumsi/prinsip-prinsip dasar yang lebih konkrit. Asumsi-asumsi dasar tersebut antara lain adalah mengenai: (a) basis pengetahuan; (b) objek material; (c) gejala yang diteliti; (d) ilmu; (e) ilmu sosial-budaya/alam; (f) disiplin. Disiplin profetik adalah cabang ilmu tertentu dalam konteks ilmu pada umumnya, tetapi ditambah dengan ciri profetik. Oleh karena itu disiplin profetik ini dapat dibangun dari disiplin ilmu konvensional (umum), sehingga kita dapat memiliki ilmu kedokteran profetik, ilmu kehutanan profetik, ilmu teknik profetik, ilmu farmasi profetik, sosiologi profetik, Ilmu Hukum Profetik, psikologi profetik, antropologi profetik, dan seterusnya.37 Dengan mengikuti alur pikir yang demikian, Ilmu Hukum Profetik adalah cabang Ilmu Hukum yang dibangun berdasarkan basis ajaran Islam yang bersumber pada al-Quran dan Sunnah Rasul yang ditransformasikan dan diobjektivkan menjadi asumsi-asumsi dasar dalam membagun teori, doktrin, asas-asas, kaidah dan norma-norma hukum, yang dapat berdampingan dengan Ilmu Hukum pada umumnya. 37 Heddy Shri Ahimsa-Putra. Op.Cit. 108 Landasan Ontologi... BAB 4 LANDASAN EPISTEMOLOGI ILMU HUKUM PROFETIK A. Pengantar Landasan epistemologi dihadirkan di hadapan kita untuk menjelaskan bagaimana pengetahuan yang disebut ilmu itu diperoleh secara benar (valid), terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan suatu metode ilmiah tertentu. Melalui epistemologi tersebut kita dapat memahami bagaimana ilmu itu ada atau lahir dan informasi atau pengetahuan yang disampaikan diyakini kebenarannya secara ilmiah. Melalui epistemologi itu juga kita dapat membedakan mana pengetahuan yang disebut ilmu dan yang bukan ilmu, mana yang ilmiah dan mana yang tidak ilmiah. Dalam epistemologi ilmu, hal mendasar yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana proses yang memungkinkan diperolehnya pengetahuan yang disebut ilmu? Bagaimana prosedur memperolehnya? Hal-hal apa yang harus diperhatikan agar kita mendapatkan pengetahuan yang benar? Apa yang disebut kebenaran itu sendiri dan apa kriterianya? Cara/teknik/sarana apa yang membantu kita dalam mendapatkan pengetahuan yang benar yang berupa ilmu itu? Untuk menjelaskan tentang landasan kefilsafatan terkait epistemologi Ilmu Hukum Profetik, terlebih dahulu akan dicoba dipaparkan dasar-dasar epistemologi ilmu yang diturunkan dari 110 Landasan Epistemologi... wawasan ajaran ke-Islaman yang ditulis oleh M.Koesnoe, dasar-dasar epistemologi al-Qur’an tentang pengembangan ilmu pengetahuan yang ditulis oleh M.Syamsudin, kemudian dilanjutkan pada tulisan M.Amin Abdullah yang menguraikan tentang epistemologi hukum Islam melalui pendekatan sistem. Dari uraian-uraian tersebut pada bagian akhir akan dicoba untuk dirumuskan tentang basis epistemologi Ilmu Hukum Profetik. B. Meninjau Pemikiran Ilmu, Ilmiah Modern dan Dasar Filsafatnya Dewasa Ini, Suatu Tinjauan dalam Rangka Persepektif Wawasan Ajaran Ke-Islaman Oleh M. Koesnoe 1. Pendahuluan (1) Di dalam masyarakat kita dewasa ini terjadi kekaburan di dalam memberi arti pada kata ilmu dan ilmiah. Terutama terhadap istilah ilmiah terjadi suatu penggunaan yang sembarangan saja. Setiap uraian dari seseorang yang menyandang gelar akademis, atau yang memangku suatu jabatan tinggi, yang disampaikan di muka suatu pertemuan yang diseleng-garakan oleh perguruan tinggi atau lembaga sejenis dengan itu, selalu dikatakan bahwa uraian yang bersangkutan disebut sebagai ‘pidato’ atau ‘orasi’ ilmiah. Kekaburan semacam itu membawa akibat, pertama-tama akan menyulitkan untuk memberi jawaban tentang bagaimana memandang dan menilai kegiatan dalam rangka kebebasan ilmiah dan kebebasan akademis yang harus dilaksanakan oleh suatu lembaga ilmiah yang oleh undang-undang dilindungi. Kesulitan tersebut akan membawa ide yang dapat menyesatkan dalam menentukan ukuran tentang bagaimana menilai suatu karya intelektual/akademis sebagai bermutu ilmiah atau tidaknya. Bab 4 111 Sehubungan dengan itu dalam kesempatan ini, pertama-tama saya ingin membahas hal tersebut. Bagi para peserta program S2 dan S3 dan para pengasuhnya, kiranya penjelasan tentang persoalan tersebut sangat diperlukan. Karena di dalam program itu, yang terutama menjadi tujuannya ialah berusaha meningkatkan penguasaan dan kemampuan para pesertanya untuk dapat bekerja secara ilmiah menurut ukuran yang dapat diakui, diterima dan dihargai sebagai layaknya suatu karya ilmiah oleh dunia ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dengan penguasaan itu, para peserta program S2 dan S3 sebagai peserta graduate program dari sesuatu lembaga pendidikan tinggi, yang bila telah selesai mengikuti program itu dengan hasil baik, dan nantinya menyandang gelar akade-mis yang tinggi, akan dapat diterima sebagai anggota masya-rakat akademis yang disegani, karena dapat ikut serta mengembangkan secara mandiri dan bermutu tentang ilmu yang menjadi perhatiannya. Hal itu karena semata-mata dia sanggup menghadapi tantangan kalangan ilmu yang ditekuninya itu secara tangguh, memuaskan serta meyakinkan. 2. Tatanan Pemikiran Menuju ke Pemikiran Ilmu dan Ilmiah Pemikiran ilmu beserta pemikiran ilmiahnya dalam sesuatu bidang, bukanlah pemikiran yang berdiri sendiri. Di belakang ilmu beserta pemikiran ilmiahnya, berdiri sebagai dasar dan pedoman, pemikiran yang lebih mendasar lagi sifatnya. Di bawah ini, secara ringkas ditunjukkan bagaimana urutan tata susunan pemikiran, baik yang merupakan pemikiran yang pra-maupun yang pasca-ilmu beserta pemikiran ilmiahnya. 1) Filsafat, terutama yang epistemologi, 2) Dari filsafat itu lahir ajaran mengetahui yang di dalamnya terdapat ajaran tentang methodologi, 3) Dari ajaran methodologi disusun ilmu pengetahuan, 4) Dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan disusun teknologinya, 5) Dari teknologi disusun penerapannya atau tekniknya. 112 Landasan Epistemologi... Demikian tata urutan pemikiran ilmu dan ilmiah. Itu adalah berpangkal dari filsafat. Di situ tampak, bahwa pemik-iran ilmu, letaknya baru pada tahap ketiga. Karena pemikiran ilmu beserta pemikiran ilmiahnya baru mungkin dilakukan atas dasar petunjuk tentang jalan pemikiran yang bagaimana yang harus ditempuh dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Artinya jalan pemikiran itu menuruti instruksi atau disiplin yang ada di dalam ajaran mengetahui tentang sesuatu menurut bidang ilmu pengetahuan yang bersangkutan secara filosofis dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dari itu dikatakan, bahwa filsafat adalah induk dari segala ilmu pengetahuan. Pemikiran ilmu beserta pemikiran ilmiahnya ialah pemikiran yang secara konsekuen mengikuti suatu disiplin berpikir yang diajarkan oleh filsafat pengetahuan. Dari itu, suatu ilmu pengetahuan juga sering disebut sebagai suatu disipiin. Pemikiran ilmu, sekali lagi yaitu hanya berpikir secara ilmu saja, adalah pemikiran terhadap sesuatu persoalan tertentu dengan mengikuti suatu metode tertentu. Pemikiran yang demikian dilakukan dengan teliti dan hati-hati, sehingga sebagai hasilnya akan dapat menguasai persoa-lan beserta jawaban atas persoalan yang bersangkutan dengan sebaik-baiknya. Dalam melaksanakan pemikiran menurut ilmu, berlaku sikap pemikiran yang dogmatis. Artinya berpangkal dari prinsip-prinsip yang sudah ditentukan terlebih dahulu pangkal haluannya di dalam menjelaskan persoalan beserta isi jawaban persoalan ilmu yang bersangkutan. Karena berpikir secara ilmu adalah berpikir untuk dapat memperoleh pengertian yang sebaik-baiknya, sejauh-jauhnya dan sedalam-dalamnya dalam arti conceptual status quo tentang apa yang telah dihasilkan oleh ilmu yang bersangkutan. Orang yang menguasai ilmu dengan cara demikian, dinamakan sebagai ahli ilmu, atau disingkat ilmuwan. Berpikir secara ilmu, berlainan dengan berpikir secara ilmiah. Beda antara keduanya pertama-tama ialah dalam sikap. Di dalam berpikir Bab 4 113 menurut ilmu, sikap yang diambil ialah menerima dan mengikuti apa yang sudah diketahui dan tercantum sebagai penjelasan atas persoalan, metode pendekatan dan kesimpulannya dalam ilmu yang bersangkutan. Dari itu sikap seorang ilmuwan sedikit banyak adalah pasif dalam menghadapi persoalan, metode dan kesimpulan yang sudah ada dalam ilmunya. Dalam menghadapi persoalan, metode pendekatan dan kesimpulan yang ada dalam bidang ilmunya, ilmuwan menjalankan kegiatannya dengan jalan yang bersifat dogmatis dalam rangka menguasai isi ilmu yang bersangkutan atas dasar pikiran conceptual status quo. Sikap ilmiah adalah meragukan, baik pangkal haluan yang telah diambil, tentang persoalannya, tentang metode pendekatannya ataupun tentang kesimpulan yang dikemukakan di dalam ilmu yang bersangkutan. Dalam pemikiran ilmiah itu keraguan dapat ditimbulkan karena dilihat adanya kelemahan-kelemahan dalam pemikiran yang dilakukan didalam mengajukan pangkal haluannya, atau dalam persoalan yang diajukan. Dapat pula karena dilihat adanya ketidak beresan dalam menjalankan metode pendekatan atas persoalannya itu menurut disiplin berpikir yang berlaku dalam ilmu yang bersangkutan. Dengan demikian kesimpulan yang diperolehnya dinilai sebagai kurang tepat, atau tidak sesuai. Dengan diragukannya itu, kesimpulan yang telah ada di dalam ilmu tersebut membawa persoalan baru lagi menurut pandangan ilmiahnya. Dengan begitu secara ilmiah masih mungkin dapatnya kesimpulan tersebut dipindahkan cakrawalanya ke cakrawala atau dimensi yang lebih jauh dan lebih dalam. Dengan demikian pemikiran ilmiah, adalah pemikiran yang dinamis dalam kerangka proses mengetahui ke arah yang lebih jauh atau lebih dalam menurut disiplin berpikir dalam ilmu yang bersangkutan. Gerak itu tak kenal berhenti pada satu titik kesimpulan yang telah dicapai. Di dalam pemikiran ilmiah memang tidak ada kesimpulan akhir. Hal itu adalah dibawa oleh watak ‘tahu’ itu sendiri. Watak dari tahu ialah terus berubah. Apa yang kini diketahui, besok sudah lain lagi. Mungkin sebagai tambahan, dan mungkin sebagai sesuatu yang 114 Landasan Epistemologi... berlainan. Dengan rumusan lain: tahu adalah selalu berada dalam proses. Proses artinya terus berubah. Dari itu pemikiran ilmiah adalah suatu pemikiran dinamis, yang pada waktunya selalu mengeluarkan suatu pendapat baru yang bersifat orisinil di dalam bidang pengetahuan yang bersangkutan. Pikiran baru itu baik mengenai rumusan pangkal haluannya, mengenai persoalannya, ataupun mengenai metode pendekatan persoalan yang bersangkutan, ataupun mengenai kesimpulannya sebagai jawaban dari persoalan yang bersangkutan. Pemikiran baru tersebut sebagai hasil pemikiran ilmiah tidak berhenti sampai pada suatu kesimpulan saja. Terhadap suatu pendapat yang sudah ada, di dalam pemikiran ilmiah akan selalu terjadi koreksi, penyangkalan, falsifikasi dan verifikasi sehingga membawa pemikiran ilmiah tidak pemah selesai. Dengan demikian, pemikiran ilmiah berlainan dengan pemikiran ilmu yang bersifat status quo. Pemikiran ilmiah adalah pemikiran yang selalu menjalankan gerak untuk searching forever, dan karenanya merupakan pemikiran yang terus menerus berupaya ingin memperbaharui atau ingin memindahkan cakarawala atau dimensi tahu dalam ilmunya ataupun ingin menempatkan ke cakrawala atau ke dalam dimensi yang lebih dalam dari persoalan dan jawaban ilmu yang dihadapinya. Sehubungan dengan itu, bagi mereka yang bergerak di dalam suatu keilmuan dengan sikap dan tindakan ilmiah yang demikian, ada sebutan khusus yang kini sudah tidak diterima di dalam bahasa kita. Istilah tersebut, kini sudah tidak dipakai lagi, yaitu sebutan ilmiawan. Dari uraian di atas, antara ilmuwan dan ilmiawan, dalam dasarya terdapat perbedaan yang prinsipiil. Penghapusan istilah “ilmiawan” dari kamus bahasa kita, yang dilakukan karena tidak sesuai dengan tata bahasa Indonesia kita yang baik dan benar, karenanya merupakan suatu kemunduran dalam pandangan tentang ilmu dan ilmiahnya. Catatan: Alasan bahwa istilah ilmiawan yang sudah begitu terkenal dan hidup di dalam masyarakat kita pada masa yang silam, mulai tahun tujuhpuluhan dinyatakan sebagai suatu istilah yang salah bilamana dilihat dari segi tata-bahasa kita yang baik dan benar. Alasan tersebut, menurut hemat saya kurang kena. Karena di dalam bahasa manapun, Bab 4 115 sesuatu pernyataan bahasa tidak selalu secara eksak mengikuti ilmu tata-bahasanya. Ilmu tata bahasa lahir, baru setelah ada bahasa. Dari itu pasti ada di antaranya penyimpangan-penyimpangan terhadap penggunaan bahasa diukur dari ilmu tata bahasa yang bersang-kutan. Dari tata urutan di atas terlihat, bahwa teknologi, tempatnya berada setelah ilmu pengetahuan. Hal ini sering tidak disadari oleh banyak kalangan kita. Teknologi adalah bidang kegiatan pemikiran yang menggarap bagaimana suatu hasil kegiatan ilmiah dapat dirumuskan jalannya untuk dapatnya hasil ilmiah yang bersangkutan dilaksanakan di dalam kenyataah empiris melalui teknik-teknik tertentu. Karenanya teknologi tidak digolongkan ke dalam pemikiran ilmiah. Kegiatan teknologi yang demikian diberi sebutannya tersendiri yaitu ‘pengembangan’. Hal itu karena kegiatan pemikiran dalam teknologi adalah menemukan rumusan jalan merealisir hasil ilmiah itu sesuai dengan perubahan hasil-hasil ilmu pengetahuan yang bersangkutan. 3. Hubungan Pemikiran Ilmu dan Ilmiah dengan Filsafat Ilmu beserta kegiatan pemikiran ilmiahnya, selalu berawal pada sesuatu pangkal haluan yang ditentukan dalam menangani sesuatu hal. Dari pangkal haluan yang bersangku-tan disusun terlebih dahulu persoalannya. Dengan persoalan yang diajukan itu ilmu pengetahuan berusaha untuk menjawabnya dengan memperhatikan disiplin pemikiran sebagai methode yang harus ditempuhnya. Metode yang ditentukan itu adalah guna sampai kepada perolehan jawaban sebagai kesimpulan umum yang bebas dari persyaratan-persyaratan yang ditimbulkan oleh keadaan-keadaan yang khusus dalam persoalan yang bersangkutan yaitu yang berujud sebagai apa yang dinamakan ‘teori’. Sebagai contoh: ilmu alam selalu berawal dari pangkal haluan tentang alam yang sudah ditetapkan pendiriannya. Kemudian disusun persoalan-persoalan tentang benda alam. Persoalan itu digarap sebagai usaha menjelaskan tentang benda alam yang bersangkutan dalam berbagai kondisinya yang mungkin. Tetapi ilmu ini tidak berusaha 116 Landasan Epistemologi... menentukan apa sebenarnya yang dikemukakan sebagai ‘benda alam’ yang dihadapinya itu. Lebih-lebih ilmu pengetahuan alam tidak akan menjelaskan apa sebenarnya alam itu? Contoh lain yaitu Ilmu Hukum. Ilmu ini membahas segala persoalan dari hukum. Tetapi Ilmu Hukum tidak mempersoalkan apa sebenarnya yang dinamakan hukum itu. Filsafat justru menanyakan tentang dasar-dasarnya tentang apa yang diajukan di dalam lingkungan persoalan ilmu pengetahuan. Yang dihadapi oleh filsafat ialah dasar-dasar dari yang oleh ilmu pengetahuan sudah dengan begitu saja diterima dan dijadikan sasaran beserta persoalannya. Filsafat berusaha menjelaskan tentang dasar-dasar dari pemikiran ilmu dan ilmiahnya itu. Penemuan filsafat tentang itu kemudian dimanfaatkan dan dipergunakan ilmu sebagai sasaran untuk penggarapan ilmu yang bersangkutan menurut petunjuk dari ajaran berilmu, khususnya metodologi dalam filsafat yang bersangkutan. Selanjutnya filsafat menunjukkan sampai dimana dan bagaimana validitas pengetahuan yang ada pada manusia. Bagaimana membangun sesuatu pengetahuan yang dapat dipertanggung jawabkan menurut ukuran kebenaran filsafat yang dianutnya dengan mengikuti secara konsekwen ajaran ‘metodologi’ nya. 4. Dasar Filsafati Pemikiran Ilmu dan Ilmiah Modern Pemikiran ilmu dan ilmiah modern yang kini kita kenal dan kita ikuti, adalah berkat berkembangnya suatu filsafat yang disebut fllsafat epistemologi. Filsafat ini memusatkan pemikirannya untuk menemukan jawaban atas pertanyaan tentang bagaimananya dan sejauh mana validitas kemampuan tahu yang ada pada manusia. Di dalam filsafat epistemologi, sasaran pemikirannya yang radikal terarah pada manusia sebagai subjek yang memikir itu sendiri. Dari itu filsafat epistemologi juga disebut sebagai filsafat yang subjektivistis. Di dalam lingkungan filsafat itu terdapat pemikiran tentang bagaimana kita dapat mengetahui sedemikian rupa sehingga hasilnya Bab 4 117 dapat diterima menurut ukuran kebenaran yang sesuai dengan pandangan filsafat yang bersangkutan. Hasil pemikiran itu dituangkan ke dalam suatu ajaran menge-tahui yang disebut sebagai ‘ajaran metodologi’. Ajaran ini yang membawa kepada adanya suatu instruksi berpikir dalam melakukan kegiatan keilmuan. Instruksi berpikir semacam itu sebagai telah disinggung diatas disebut dengan istilah disiplin. Ajaran mengenai metodologi, di dalam sejarah pemikiran filsafat di Eropa Barat terdiri dari dua aliran yang prinsipiil berbeda. Perbedaan prinsipiil itu dasar-dasarnya sudah tampak sejak zaman Yunani Kuno, yang ditunjukkan dalam pendirian Plato tentang pengetahuan manusia dan pendirian muridnya yaitu Aristoteles tentang hal tersebut. Menurut Plato, pengetahuan yang ada pada manusia, tidak lain adalah merupakan bayangan, suatu kopi dalam pikiran kita tentang apa yang ada di dalam alam luar kita yaitu alam ‘idee’. Di dalam alam idee yang metaphysis itu, segala sesuatu mempunyai wujudnya yang tetap dan abadi. Lain lagi Aristoteles. Ia berpendirian, bahwa pengetahuan kita bersumber dari ‘hal’ yang konkrit yang kita hadapi. Dari pendirian kedua pemikir Yunani Kuno tersebut tampak, bahwa Plato meletakkan dasar mengetahui yang bersifat metaphysis, sedangkan Aristoteles meletakkan dasar mengetahui yang realistis konkrit, artinya yang empiris. Perbedaan pendirian antara guru-murid tersebut dalam dasarnya merupakan perbedaan dalam filsafat yang dianut masing-masing mengenai hakikat dari totalitas ini. Perbedaan pendirian filsafatnya itu adalah perbedaan dalam filsafat ontologinya. Setelah abad pertengahan di Eropa Barat, pemikiran filsafat beralih dari pemikiran ontologi ke pemikiran epistemologi. Perbedaan pendirian antara Plato dan Aristoteles yang pada dasarnya merupakan perbedaan dalam ontologinya, pada waktu itu mulai bergeser. Dari pandangan tentang ontologinya, (artinya filsafat tentang hakikat kebenaran dari obyek yang menjadi pokok pemikiran) menjadi pemikiran epistemologi, yaitu pemikiran tentang subjek yang memikir itu sendiri. 118 Landasan Epistemologi... Di dalam pemikiran epistemologi, yang sentral menjadi sasaran pemikiran filsafat adalah manusia sebagai subjek yang memikir. Dalam hal ini yang ditanyakan ialah bagaimana manusia sampai dapat mengetahui segala sesuatu? Dalam menghadapi pertanyaan itu filsafat epistemologi di daratan Eropa Barat memberi jawaban, bahwa itu adalah karena pada manusia ada ‘pikiran’. Sekali lagi ‘pikiran’. Itu yang yang merupakan alat dan sekaligus sumber dari pengetahuan manu-sia, dan pikiran itu adalah sesuatu yang metaphysis. Dari itu epistemologi yang dianut oleh para pemikir di daratan Eropa Barat adalah epistemologi yang metaphysis. Aliran yang demikian ini adalah aliran dalam rangka pendirian Plato. Lain lagi epistemologi yang dianut oleh kalangan pemikir di Inggris. Kalangan itu mengikuti aliran Aristoteles yang realistis. Pemikir epistemologi Inggris tergolong pemikir yang mengikuti dan berpegangan kepada epistemologi yang empiris. Perbedaan dasar-dasar dalam epistemologinya itu membawa pula perbedaan dalam cara berpikir ilmiahnya. Di daratan Eropa Barat diutamakan segi metaphysisnya. Pengutamaan pandangan metaphysis itu menentukan pendekatan di dalam ajaran berilmu pengetahuan. Atas dasar pandangan itu, pendekatan keilmuan di daratan Eropa Barat menganut pendekatan yang bersifat deduktip-spekulatip. Di Inggris diutamakan segi empirisnya. Dari itu keilmuan dilakukan dengan mengutamakan pendekatan yang kausal-empiris-analitis. Perbedaan mengenai aliran epistemologi antara daratan Eropa Barat dan Inggris, tidak saja membawa perbedaan dalam tekanan perhatian dalam berilmu beserta jalan pendekatan berilmu. Perbedaan tersebut juga membawa perbedaan dalam hal tujuan dalam berpengetahuan. Di daratan Eropa Barat, tujuan berpengetahuan ialah seperti yang sejak abad pertengahan dikemukakan oleh Thomas van Aquino yaitu dalam rangka “memenuhi panggilan jiwa manusia yang selalu ingin mengetahui”, atau dalam rumusan bahasa Latin desiderium sciendi. Di Bab 4 119 Inggris, seperti dikemukakan oleh oleh Francis Bacon, tujuannya didasarkan kepada pandangan bahwa knowledge is power, pengetahuan adalah kekuasaan. Perbedaan pendirian mengenai tujuan berilmu, menunjukkan pula perbedaan filsafat hidup yang melatar belakanginya. Di daratan Eropa Barat, filsafat hidup yang menjadi latar belakangnya ialah ‘penyempurnaan manusia’, sedang di Inggris yang melatar belakanginya adalah faham hedonisme, atau eudemonisme yaitu yang jiwanya sebagaimana dirumuskan Adam Smith yaitu untuk menjelmakan the greatest happiness for the greatest number. Kemudian filsafat ini di Amerika Serikat dikembangkan menjadi filsafat pragmatisme, yang di dalam kejiwaannya, seperti yang dirumuskan secara ringkas oleh William James yaitu untuk memenuhi keinginan the satisfaction of human wants. Baik di daratan Eropa Barat, maupun di Inggris, sekalipun antara keduanya dalam hal pandangan epistemologinya ada prinsip-prinsip yang berbeda, namun antara keduanya ada juga kesamaannya. Antara kedua aliran itu dalam hal semangat yang mendasari filsafat epistemologinya sama-sama hanya mengandalkan kepada kemampuan yang ada pada diri manusia saja. Di daratan Eropa Barat kekuatan tahu itu berkat adanya pikiran manusia saja. Cogito ergo sum, saya berpikir, karena itu saya ada, kata Rene Descartes. Di Inggris ditekankan kepada pengalaman, experience is the best teacher. Selain itu kedua-duanya di dalam epistemologinya juga menunjukkan kesamaannya yaitu bahwa filsafat epistemologinya itu sama sekali terlepas dari faham Ketuhanan yang diajarkan oleh gereja. Di dalam pengembangan filsafat Hukum, hal ini tampak jelas dalam ucapan Hugo Grotius yang bunyinya adalah sebagai berikut: etiamsi daremus non esse Deum, artinya di dalam memikirkan Hukum Kodrat, ‘anggaplah seolah-olah Tuhan itu tidak ada.’ Eropa Barat setelah abad pertengahan, dengan berpedoman kepada filsafat epistemologi yang hanya mengandalkan ‘pikiran’ saja, atau mengandalkan “pengalaman” saja, mengembangkan ilmu pengetahuan 120 Landasan Epistemologi... dengan menanggalkan sama sekali faham Ketuhanan yang diajarkan gereja dalam abad-abad sebelumnya. Abad ke XVIII dapat dikatakan bahwa terutama bagi daratan Eropa Barat merupakan abad ‘pikiran’, atau abad ‘rasionalisme’. Eropa Barat dengan jiwa itu memasuki sejarah baru yaitu timbulnya awal kapitalisme, awal industrialisasi serta awal kemajuan ilmu pengetahuan dan filsafat. Pengembangan ilmu pengetahuan pada masa itu, yang didorong oleh berkembangnya filsafat epistemologi, dasardasarnya yang perlu dicatat di sini ialah: 1) Filsafat epistemoiogi lepas dari faham Ketuhanan sebagaimana yang diajarkan gereja dalam abad-abad sebelumnya. 2) Filsafat epistemologi dipusatkan kepada kemampuan pikiran atau pengalaman manusia saja, 3) Faham kemanusiaan berarti individualisme dimana dijunjung tinggi hak dan kebebasan individu, 4) Dengan prinsip itu setiap individu bebas mengembangkan diri pribadinya dengan kemampuan pengetahuannya untuk memenuhi tuntutan tujuan hidupnya yang sesuai dengan filsafat hidup yang dianutnya. Pengembangan ilmu pengetahuan yang dibangun dan dikembangkan semata-mata dengan mengandalkan pada kekuatan mengetahui manusia yaitu pikiran saja atau empiri saja, ternyata pada permulaan abad ke XIX, mulai meluntur. Perkembangan selanjutnya dari filsafat yang demikian mulai mendapat tantangan. Di daratan Eropa Barat tantangan tersebut terutama dibawa oleh perkembangan aliran romantik dan filsafat kritis. Dengan itu timbul ketidak puasan terhadap pengembangan filsafat dan ilmu pengetahuan yang mengutamakan segi rasionilnya saja meninggalkan segi-segi etik, aestetika, dan lain-lain nilainilai kejiwaan yang tidak masuk di dalam alam akal atau empiri. Memasuki abad ke XX, terjadi lagi suatu pembaharuan dalam filsafat di daratan Eropa Barat. Filsafat tersebut tidak mengikuti filsafat objektip yaitu filsafat ontologi dan juga tidak mengikuti filsafat subjektip yaitu filsafat epistemologi. Aliran baru ini mengajukan pandangannya sendiri dimana subjek-objek disatukan. Bab 4 121 Filsafat ini mengajarkan bahwa alam nyata harus dibedakan dari “keadaannya” atau existensinya. Existensi alam nyata ini adalah tidak tetap. Itu tunduk kepada perubahan-perubahan yang terus menerus. Perubahan itu terjadi bilamana keadaan dari alam nyata itu mencapai suatu ‘garis batas’ dari keadaannya. Di dalam istilah filsafat di Jerman garis batas keadaan dari sesuatu itu disebut dengan istilah ‘Grenzsituation’. Karena aliran filsafat ini mengutamakan pada keadaan alam nyata, maka filsafat ini dinamakan sebagai filsafat existensialisme. Batas-batas semacam itu juga berlaku bagi manusia sebagai bagian dari alam nyata. Dari itu, manusia di dalam keadaannya perlu memperhitungkan garis-garis batasnya tersebut. Itu penting dalam hal dia ingin memberi makna kepada dirinya sendiri tentang ‘keberadaannya’ di dalam alam nyata ini. Tampak di sini filsafat tersebut menunjukkan suatu filsafat yang sangat individualistis. Tentang pertanyaan, apakah filsafat existensialisme terlepas dari faham Ketuhanan atau tidak, sulit untuk dijawab secara ringkas di sini. Karena diantara aliran-alirannya yang ada, terdapat aliran yang ada hubungannya dengan faham Ketuhanan. Perkembangan selanjutnya dari filsafat Barat ialah timbulnya akhirakhir ini filsafat postmodernisme. Filsafat ini bersifat irrasionil. Dalam ajarannya filsafat ini menentang foundationalisme, essentialisme dan realisme. Bukan maksudnya di dalam kesempatan ini membahas perkembangan aliran-aliran filsafat Barat tersebut. Yang ingin dikemukakan di sini hanya bagaimana garis besar perkembangan Filsafat Barat terutama filsafat epistemologi sebagai pencetus dan pemberi dasar lahirnya dan pengembangan ilmu dan pemikiran ilmiah yang hingga kini kita jumpai dan ikuti. Sudah barang tentu perkembangan filsafat selanjutnya seperti existensialisme dan post modernisme, juga mempengaruhi dan menentukan keilmuan dan pemikiran ilmiah modern dewasa ini. Akan tetapi, bila itu juga dibahas di sini, akan terlalu panjang dan memakan 122 Landasan Epistemologi... waktu yang tidak sedikit. Dari itu, pembahasan tentang ilmu, keilmiahan dan dasar-dasar filsafatnya dewasa ini kita cukupkan sampai disini saja. Dasar filsafat ilmu dan keilmiahan sebagaimana telah disinggung di atas, secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut: 1) Zaman kuno dan abad pertengahan: filsafat ontologi. Bagi Eropa Barat filsafat ini menyuburkan ilmu yang dasar dan sumbernya ialah faham Ketuhanan menurut ajaran gereja, 2) Zaman baru: filsafat epistemologi. Bagi Eropa Barat dan lain-lain bagian dari dunia ini membawa kepada dianutnya faham rasionalisme dan empirisme, yang membawa kemajuan di dalam ilmu dan pemikiran ilmiah dengan sepenuhnya mempercayakan kepada kekuatan pikiran dan empiri manusia. Dalam filsafat epistemologi ini dipisahkan ilmu dan keilmiahan dari faham ketuhanan yang diajarkan gereja, 3) Zaman modern: filsafat irrasionalisme. Bagi ilmu dan keilmiahan membawa kepada suatu arah yang tidak lagi menentu. Untuk sedikit penjelasan tentang tidak menentunya arah ini, filsafat ilmu itu sendiri kini menunjukkan adanya pandangan yang bercabangcabang tentang bagaimana ilmu dan keilmiahan itu. Terutama hal itu tampak dalam menghadapi pertanyaan tentang dari mana filsafat pengetahuan akan memulai ajarannya tentang mengetahui. Tentang itu kini terdapat bermacam macam jawaban yang plural. Pangkal dasar yang dulu diletakkan oleh Plato yaitu alam idee dan Aristoteles yaitu pada halnya yang konkrit, kini telah berkembang sedemikian rupa sehingga pangkal dasar untuk mengetahui menjadi bermacam-macam jenisnya. Hal itu dapat ditunjukkan kepada pertanyaan-pertanyaan yang kini timbul tentang dari mana mulai mengetahui itu. Antara lain yang dapat dikemukakan ialah pertanyaanpertanyan sebagai berikut: 1) Apakah berpangkal dari pikiran seperti ditegaskan oleh Descartes, ataukah pada pengalaman? Kalau berpangkal dari pengalaman apa itu berupa empiri seperti yang dikemukakan oleh John Locke, atau apa yang ‘kasat indera’ atau yang sensual, seperti yang dikemukkan oleh David Hume?; Bab 4 123 2) Apakah berpangkal dari Idee seperti dikemukakan oleh Berkley atau Hegel? Ataukah berpangkal dari materi seperti dikemukakan antara lain oleh Marx dan lain-lain penganut materialisme?; 3) Ataukah berpangkal dari awal kemampuan tahu manusia yaitu yang: a priorie seperti yang dikemukakan Kant? Ataukah dari phenomena yang dikemukakan oleh Husserl yang oleh Wittgenstein ditegaskan sebagai yang berujud dalam bahasa? Di dalam perkembangannya, segala dasar-dasar untuk memulai guna mengetahui tersebut, kemudian mendapat sanggahan yang selanjutnya menghasilkan timbulnya pandangan baru yang dinamakan Kritische Rationalisme seperti yang dikemukakan oleh Popper. Selanjutnya pikiran ini pun kemudian disusul dengan timbulnya pandangan yang lain dari Kritische Rationalisme yaitu pandangan seperti dikemuka-kan oleh Jurgens Habermas yang disebut sebagai Kritische Theorie. Gambaran di atas hanya sekedar ingin menunjukkan tentang perkembangan filsafat pengetahuan dewasa ini yang terus berganti dan tidak jelas arah yang ditempuhnya. Tetapi bagaimanapun, pengembangan ilmu dan keilmiahan modern dalam abad ke XX ini tidak terlepas dari pengaruh semangat dan kejiwaan yang didasari oleh filsafat yang menjiwai abad ke XVIII yang masih hidup dalam awal abad XIX. Dasar-dasar dan benih-benih pemikiran ilmu dan keilmiahan yang diajarkan oleh filsafat epistemologi pada masa itu, tetap berperan penting karena pada masa itu lahirnya apa yang dinamakan ‘teori besar’ dari ilmu pengetahun yang sampai kini tetap kita kenal dan menjadi perhatian. Pemeliharaan keilmuan dan keilmiahan tetap mengandalkan terutama kepada kekuatan ‘pikiran’ atau ‘empiri’ manusia saja dengan meninggalkan faham ‘Ketuhanan’. Jiwa yang demikian, ilmu dan keilmiahan Eropa Barat memasuki abad ke XX, menyeret dunia di dalam pemeliharaan dan pengembangan ilmu dan keilmiahannya sampai kini. Selain itu, di dalam abad ke XX ini, kedua macam filsafat yang kuat dianut di Eropa yaitu filsafat yang metaphysis yang begitu kuat hidup didaratan Eropa Barat, maupun filsafat yang empiris yang berkembang di Inggris dan Amerika Serikat, 124 Landasan Epistemologi... menunjukkan bahwa filsafat empiris beserta sistim pemikiran yang kausal-empiris-analitis pada akhir-akhir ini yang menunjukkan pengaruhnya yang lebih populer dan dominan. Filsafat empirisme, sebagai disinggung di atas, tidak saja mengajarkan bagaimana berpengetahuan. Tetapi filsafat itu juga mengandung filsafat hidup pula yang dasarnya ialah empiris. Filsafat hidup atas dasar empirisme ini, yaitu filsafat hedonisme, pada bagian akhir abad ke XIX, di Amerika Serikat berkembang menjadi filsafat pragmatisme dengan dasar-dasar yang materialistis. Filsafat hidup itu kini yang menguasai kehidupan kemanusiaan dengan kuat dalam skala ‘global’. Filsafat itu yang kini menjadi jiwa dan landasan dari apa yang kini secara populair disebut ‘globalisasi’. Catatan: Dewasa ini, dengan enak kita menyebut tentang adanya ‘globalisasi’. Kosa kata itu adalah suatu kata benda yang di dalamnya ada isinya, yaitu proses. Dengan sebutan itu jadinya kita hanya menyebut suatu benda yang isinya ialah suatu proses. Mengenai proses tentang apa, tidaklah dijelaskan dengan sebutan yang begitu populer itu. Dari itu perlu ditentukan bahwa ‘globalisasi’ menurut hemat saya adalah suatu peristiwa berisi proses yang membawa kemanusiaan di seluruh dunia untuk menerima dan menganut jiwa hedonisme yang materialistis individualitis dengan mengikuti pemikiran yang kausaalempiris-analistis. Secara ringkas dan pokok-pokok, jiwa dan semangat hedonisme modern itu, yang menjiwai apa yang kini disebut dengan istilah populer “globalisasi”, pokok-pokok isinya ialah sebagai berikut: 1) Hedonisme sebagai pragmatisme yang bertujuan untuk mencapai kehidupan yang kaya, bermewahan, tenar dan kuasa, 2) Individualistis, 3) Sekularistis, 4) Materialistis, 5) Berpemikiran yang bersifat lugas kausaal-empiris-analitis. Atas dasar filsafat ini, ilmu dan keilmiahan modern itu yang kini secara mengglobal dipelihara dan dikembangkan. Bab 4 5. Ajaran Islam tentang Pemikiran Keilmiahan 125 Pengetahuan dan Kini waktunya kita meninjau bagaimana keilmuan dan keilmiahan yang didasari oleh filsafat yang pernah dikem-bangkan di Barat, dengan latar belakang dan dasar-dasar wawasan ke-Islaman, karya para ulama yang bahan-bahannya diambil dan bersumber pada al Qur’an dan al Hadist. Uraian tentang ini, berhubung waktu, sementara kita batasi dalam pokok-pokok dan yang dasar saja. Yang penting dikemukakan di sini sebagai ancang-ancang uraian di kemudian hari, yaitu bahwa di dalam mempelajari ajaran yang terkandung di dalam al Qur’an dan Hadist, sesuai dengan perintah dalam ayat dan ajaran itu, bahwa untuk itu disyaratkan pertama-tama harus dilakukan dengan penuh iman (S.Ali Imran ayat 139). Hal ini karena iman, dalam ajaran al Qur’an merupakan cahaya yang menerangi jiwa, artinya untuk membuka jiwa dari keadaan ‘gelap’ sama sekali menjadi keadaan yang ‘terang’. Dalam upaya selanjutnya yang harus dilakukan ialah menguasai ilmu dan ma’rifat. Untuk itu menurut ajaran Islam orang tidak hanya dapat mengandalkan kepada bekerjanya kekuatan pikiran yang ada pada manusia saja. Yang perlu dipergunakan dan dilalui dalam usaha menguasai itu ialah mempergunakan sebaik-baiknya tiga kemampuan yang ada pada jiwa manusia yaitu: a. Pemikiran (tafakkarun), b. Akal (taqqilun), c. Hati (tadhabbarun). Pemikiran, artinya kemampuan rohani menggerakkan daya yang membawa seorang kepada ilmu yaitu kemampuan untuk dapat menangkap tentang sesuatu dan membedakannya dari yang lain. Akal adalah kemampuan rohani yang membawa kepada pengertian tentang bagaimana hubungan yang ditangkap oleh pikiran itu satu dengan yang lain beserta segaia konksekwensi dan kelanjutannya. Ringkasnya hikmathikmatnya. Hati adalah kemampuan rohani untuk mengetahui secara menyeluruh. Artinya apa yang diperoleh dari ilmu dan hikmat melalui 126 Landasan Epistemologi... pikiran dan akal dicakup ke dalam satu kesatuan dengan perspektifnya dari hidup dan kehidupan. Dengan demikian kesatuan ilmu dan hikmat itu ditempatkan dan berada di dalam suatu rancangan wawasan yang menyeluruh. Itu adalah kerjanya hati yaitu suatu substansi yang khas dari jiwa kemanusiaan untuk dapat menangkap dan merangkum ilmu, hikmat dan kearifan yang dikuasainya dengan kwalitas yang Ilahiyah. Wawasan tersebut, menurut al Qur’an dibedakan antara wawasan yang didasari iman, dan wawasan yang tidak didasari iman. Antara kedua macam wawasan tersebut ada perbedaan dalam cakrawala yang dapat dijangkau masing-masing. Tentang bagaimana tinjauan kita terhadap ilmu, ilmiah modern dan dasar-dasar filsafatnya tersebut, yang perlu dikemukakan di sini ialah, bahwa sampai kini hasil yang telah saya peroleh belum jauh dan belum mantap. Menyajikan hasil-hasil tersebut dalam keadaan yang bersifat masih mengantar kepada ilmu dan keilmiahan beserta dasar-dasar filsafatnya, kiranya akan merupakan penyajian yang kurang pada tempatnya. Dari itu apa yang akan dikemukakan di sini adalah hanya bahanbahan pendahuluan saja yang berguna untuk pemikiran selanjutnya untuk dapat dipergunakan meninjau ilmu dan keilmuan modern beserta dasar filsafatnya. Dalam kesempatan ini karenanya saya hanya dapat kemukakan pertama-tama bahwa sementara ini, perhatian saya masih terpusat pada beberapa ayat al Qur’an yang kita semua sudah tahu dan hafal yaitu: 1) Surat al Baqarah ayat 30-38, tentang penunjukkan manusia sebagai khalifah dibumi, 2) Surat al Alaq, ayat 1-8, tentang perintah membaca dan sebagainya, 3) Surat al Kahfi ayat 60-82, tentang nabi Musa mencari ilmu, 4) Surat alam Nasyrah, ayat 1-8, tentang sifat’ keadaan’ dan sikap yang harus kita ambil menghadapinya, 5) Surat Al Imron ayat 139, tentang pentingnya iman. Dari ayat-ayat tersebut, dapat kita tangkap tentang ilmu dan kemampuan berilmu yang ada pada manusia menurut al Qur’an sebagai berikut: Bab 4 127 1) 2) 3) 4) Bahwa ilmu itu hanya ada pada sisi Tuhan, Bahwa dengan ridhaNya, manusia diberi sedikit dari ilmu itu, Bahwa ilmu perlu didampingi pula dengan ma’rifatnya, Bahwa ilmu dan ma’rifat yang diberikan oleh Allah menjangkau dua macam dimensi alam tahu yaitu alam syahadat dan alam malakut.Ilmu dan ma’rifatnya yang hanya menjangkau alam syahadat saja adalah ilmu ‘muamalat’. Yang dapat menjangkau kedua alam sekaligus adalah ilmu mukasyafah, 5) Bahwa penguasaan setiap orang terhadap ilmu dan ma’rifatnya tersebut berbeda-beda bergantung kepada keimanan dan usahanya yang tepat dan sungguh-sungguh untuk menguasainya, 6) Bahwa penguasaan ilmu dan ma’rifat itu harus dilakukan dengan sikap yang dinamis, penuh dasar taqwa. Ini adalah hasil-hasil kesimpulan sementara yang sampai kini dapat kita tangkap dari al Qur’an tentang dasar-dasar untuk mengatakan ilmu dan ma’rifat. Kesimpulan ini ringkas dan masih perlu penjajagan secara lebih hati-hati dan terarah yang lebih mendalam. Di dalam waktu-waktu yang akan datang mudah-mudahan pendalaman penjajagan terhadap ayat-ayat tersebut dalam kerangka ilmu dan ma’rifat untuk kemudian dipergunakan meninjau ilmu dan keilmiahan modern beserta filsafat yang mendasarinya masih dapat kita lakukan. 6. Pendahuluan (2) Dalam uraian terdahulu telah disebut beberapa ayat al-Qur’an yang dapat dipandang berisi petunjuk Islam tentang ilmu dan ilmiah. Ayatayat al Qur’an yang dikemukakan itu sudah barang tentu tidak meliputi seluruh petunjuk tentang ilmu dan keilmiahan yang ada di dalam al Qur’an. Pilihan ayat-ayat al Qur’an yang disajikan di atas hanyalah pilihan menurut selera dan kebutuhan kita dalam upaya menunjukkan tentang bagaimana petunjuk al Qur’an tentang ilmu dan ilmiah yang akan kita pergunakan untuk meninjau ajaran ilmu dan keilmiahan modern yang dilatar belakangi oleh filsafat Barat. 128 Landasan Epistemologi... Bilamana ayat-ayat al Qur’an yang kita sebutkan di atas diperhatikan isi pokok-pokoknya, ayat-ayat tersebut menun-jukkan butir-butir petunjuk yang menjawab pertanyaan sebagai berikut: 1) Tentang dari mana ilmu itu ? (al Baqarah ayat:31, 32, 33), 2) Tentang apa ilmu itu ? (al Baqarah: ayat 31, 33), 3) Tentang apa perlengkapan seutuhnya dari ilmu? (al Baqarah : ayat; 34, 37, 38), 4) Tentang apa dasar ilmu yang benar? (Ali Imron: ayat 139), 5) Tentang jalan yang harus ditempuh dalam berilmu? (al Kahfirayat 60-82), 6) Tentana sikap dalam berilmu? (Alam Nasyrah: ayat 1-8), 7) Tentang sarana belajar berilmu? ( al Alaq: ayat 1-8 ). Bukanlah maksudnya di sini untuk memberikan tafsir terhadap ayat-ayat tersebut. Di sini hanya disimpulkan secara ringkas isi pokokpokok ayat-ayat tersebut, dilihat dari keperluan untuk menjelaskan bagaimana ilmu pengetahuan modern dalam lingkup pandangan yang berwawasan ke-Islaman atas dasar petunjuk al Qur’an. Dalam al Qur’an, ilmu itu adalah pemberian Allah s.w.t. kepada makhluknya. Kepada manusia, dianugerahkan ilmu beserta kelengkapannya yang seutuhnya sebagai salah satu alat untuk memikul tugas manusia sebagai ‘Khalifatullah’. Ilmu dalam artinya ini adalah suatu kemampuan manusia untuk mengetahui sesuatu makhluk, nama dan sebutannya, jenis dan perbedaannya satu dari lainnya. Selain ilmu, pada manusia dianugerahkan pula oleh Allah s.w.t. kelengkapan lainnya untuk melengkapi pengetahuan manusia tentang apa yang ditangkap ilmu. Kelengkapan tambahan itu ialah apa yang disebut ‘hikmat’. Ini adalah kemampuan manusia yang kedua yang dianugerahkan Allah s.w.t. bersamaan dengan ilmu, untuk dapatnya mengetahui sifat-sifat yang ada pada makhluk Allah yang bersangkutan, hubungannya satu dengan yang lain yang mungkin dapat terjadi beserta akibat atau konsekuensinya dan sebagainya, serta kegunaannya dari sifat dan konsekwensi dan lain-lain dari itu semua. Kelengkapan ilmu yang lain yang dianugerahkan Allah s.w.t. kepada manusia, ialah apa yang disebut ‘syahwat’ yaitu kemampuan Bab 4 129 berkeinginan yang bermacam-macam terhadap apa yang diketahuinya. Kelengkapan yang keempat ialah yang disebut ‘kalimat’, yaitu kemampuan untuk mengukur dan menilai seperti baik-buruk, bergunatidaknya dan sebagainya. Empat kelengkapan tahu itu adalah berujud dalam potensi untuk mengetahui dan yang pada setiap orang manusia. Sebagai potensi setiap macam kelengkapan itu mempunyai daya untuk berkembang yang bergantung pada pemeliharaan dan upaya mengembangkannya menurut cara, keuletan, serta arahnya untuk itu yang ditempuh oleh orang seseorang yang bersangkutan. Selain keempat kelengkapan alat tahu tersebut, ada lagi kelengkapan yang kelima, yang oleh Allah s.w.t. tidak dianugerahkan kepada sembarang orang. Kelengkapan kelima ini adalah kelengkapan yang khusus yang disebut huda (petunjuk). Ini adalah potensi mengetahui dan menguasai rancangan Ilahi tentang macam, arah dan jalan yang jelas dan pasti dan segala ciptaanNya termasuk manusia itu sendiri dari awal sampai akhir kejadiannya. Potensi mengetahui ini hanya akan dianugerahkan oleh Allah s.w.t. kepada mereka yang beriman. Dari bunyi ayat-ayat itu, pengetahuan yang ada pada manusia yang berwujud sebagai potensi mengetahui, adanya adalah di dalam suatu rancangan Ilahi yang mempunyai daya untuk berkembang, ada ukurannya dan ada arah yang sudah ditentukanNya. Potensi mengetahui yang demikian dianugerahkan oleh Allah s.w.t. atas dasar apa yang disebut ‘takdir’ dan ada pula yang melalui ‘wahyu’. Pertanyaan tentang dasar berilmu, dalam al Qur’an ditegaskan bahwa ilmu akan menjadi jauh dan kokoh jangkauannya bilamana didasari oleh iman kepada Allah s.w.t. sebagai Pencipta semesta makhluk. Dengan dasar itu akan dapat ditangkap oleh daya tahu tentang arti, tempat, potensi jarak jangkau yang lebih dari ilmu yang ada pada manusia. Ilmu yang dianugerahkan oleh Allah s.w.t. sebagai potensi mengetahui, hanya berguna untuk mengetahui bilamana itu digerakkan untuk mengetahui. Dari itu ilmu hanya berfungsi bilamana potensi 130 Landasan Epistemologi... berilmu itu digunakan dan digerakkan dengan sebaik-baiknya untuk mengetahui. Itu berarti bahwa mengembangkan ilmu harus ada usaha yang digerakkan oleh keinginan yang kuat dan sungguh untuk mengetahui. Selanjutnya dari ayat-ayat yang disebut di atas, ada pula petunjuk tentang bagaimana sikap orang yang berilmu. Dalam istilah teori pengetahuan biasa, itu disebut dengan sikap ilmiah. Sikap ilmiah adalah sikap yang selalu haus terus-menerus untuk mengejar apa yang belum diketahui. Itu adalah sikap yang ingin mengejar tanpa hentinya tentang apa-apa yang belum diketahuinya. Jalannya ialah dengan selalu merancang apa tindakan atau langkah berikutnya yang akan dikerjakan, sedang dia masih berada dalam keadaan mengerjakan sesuatu. Demikian petunjuk al Qur’an di dalam sikap berilmu. Juga dari ayat-ayat itu ditunjukkan, bahwa belajar berilmu harus dilakukan dengan mempergunakan qalam, artinya segala sesuatu itu harus digoreskan, dicatat, dicamkan sungguh-sungguh sehingga tidak hilang begitu saja setelah diketahui. Di dalam menghadapi ayat-ayat tersebut, yang perlu diingat ialah bahwa di dalam upaya memahaminya, kita tidak begitu saja dapat mengikuti pendekatan yang diajarkan oleh filsafat yaitu dengan kebebasan berfikir secara radikal, yang tidak diikat oleh sesuatu titik pangkal tertentu. Hal itu karena dalam mempelajari al Qur’an, ada persyaratan yang ditentukan secara khusus di dalam al Qur’an sendiri. Persyaratan itu adalah untuk memperoleh manfaat dari mempelajari al Qur’an yaitu hasilnya itu menjadi petunjuk atau (huda) baginya. Persyaratan yang ditetapkan al Qur’an itu dapat ditemukan di dalam permulaan surat al Baqarah. Jika ayat-ayat itu dilihat dari teori pengetahuan biasa, jadi dilihat dari metodologi, ayat-ayat tersebut dalam epistemologi dapat disejajarkan dengan prinsip-prinsip methodenlehre yang ada dalam al Qur’an. Petunjuk itu adalah untuk mencapai dengan sepertinya apa yang dikehendaki oleh Allah s.w.t. dari mempelajari al Bab 4 131 Qur’an. Tidak dipenuhi prinsip tersebut, tidak akan membawa arti bagi yang bersangkutan dalam mengkaji al Qur’an. Dewasa ini memang ada sikap yang lain dari apa yang ditentukan oleh al Qur’an dalam mempelajari dan memahami-nya. Hal ini terutama dilakukan oleh para ahli ilmu penge-tahuan Islam non-muslim. Mereka adalah pakar yang dengan sungguh dan tekun mempelajari isi al Qur’an dengan mengikuti disiplin ilmu-ilmu modern. Dalam mengkajinya, para pakar itu mengandalkan pada kemampuan daya akal-pikiran yang logis, tertib, kritis dan objektif yang mereka kuasai. Dalam mempelajari dan memahami al Qur’an dengan jalan yang demikian, mereka tidak memenuhi tuntutan prinsip-prinsip yang ditentukan al Qur’an yaitu beriman dan selanjutnya menjadikan dirinya sebagai seorang muttaqin. Sikap yang demikian dalam menemukan pemahamannya tentang isi dan arti ayat-ayat al Qur’an memberi hasil-hasil kesimpulan yang kritis dan mena’jubkan. Akan tetapi hasilnya itu tetap berujud sebagai suatu ulasan ilmiah saja yang tunduk kepada kritik. Hasil itu tidak dapat menjadi petunjuk atau huda. Hasilnya hanyalah suatu penjelasan atau pemahaman saja tentang apa isi yang termuat di dalam al Qur’an. Jadi semacam suatu ‘informasi’ tentang al Qur’an. Sikap bebas itu, sebagai sikap ilmiahnya, bilamana diperhatikan bagaimana memulai kajiannya terhadap al Qur-’an, menunjukkan bahwa itu dilakukan dengan pangkal-pikiran yang semaunya yang sesuai dengan cita-rasa pilihan idee pribadi masing-masing. Tentang bagaimana pangkal-pikiran yang mungkin diikuti, di dalam uraian yang lalu, beberapa dari padanya telah dijelaskan. Di dalam kesempatan ini yang khusus akan diperhatikan ialah suatu aliran yang berpendirian bahwa pangkal-pikiran pengetahuan itu dasarnya ialah ‘wahyu’. Aliran ini diikuti terutama dalam kalangan yang berkecimpung di dalam ‘theologi’, yaitu suatu pengetahuan yang berusaha membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Catatan: Mungkin diantara kalangan pemikir kita ada yang berpendapat bahwa aliran semacam ini sesuai untuk dipergunakan mempelajari dan 132 Landasan Epistemologi... memahami ayat-ayat al Qur’an. Karena bukankah faham ini juga berangkat dari idee kewahyuan ? Terhadap pendekatan model ini, yang tetap perlu diingat ialah bahwa model ini tetap merupakan model pendekatan yang dasarnya filsafat. Pangkal dan dasar pemikirannya sebagaimana disebutkan di atas adalah model pemikiran yang bilamana dikejar secara pemikiran filsafat menimbulkan pertanyaan yang sulit dicarikan jawabannya. Dengan titik tolak kewahyuan, dalam model pemikiran ini akan timbul serangkaian pertanyaan yang merupakan suatu lingkaran setan. Pangkal-haluan dalam pemikiran model kewahyuan ini berarti membawa pemikiran filsafat ini menuju kepada pemikiran tentang Dhat yang memberi wahyu, yaitu ‘Dhat Yang Maha Tinggi’. Bagi filsafat, Dhat tersebut akan menjadi teka-teki tersendiri. Sebagai demikian, itu akan terus dikejar dengan pertanyaan-pertanyaan untuk dapatnya diperoleh ‘clara et distincta perceptio’nya. Mungkinkah itu diberikan oleh filsafat? Jika itu tetap merupakan teka-teki filsafat, pertanyaan-pertanyaan yang timbul, yang merupakan suatu lingkaran setan itu, adalah sebagai berikut: 1) bagaimana kita harus mengetahui, dan 2) bagaimana pengetahuan kita yang dimaksud, terhadap 3) apa yang kita tidak atau belum tahu bahwa itu ada? Pertanyaan-pertanyaan itu adalah merupakan apa yang dinamakan ‘Munchhausen Trilemma’. Jika diperhatikan dengan seksama, lingkaran setan dari pertanyaan-pertanyaan itu, pada dasarnya adalah mengenai pertanyaan tentang titik pangkal yang pasti yang dipergunakan dalam pemikiran itu yaitu yang di dalam teori ilmu disebut sebagai titik Archimedes. Titik pangkal itu harus dapat berfungsi sedemikian rupa sehingga dari titik itu dapat ditarik pertanyaan-pertanyaan berikutnya beserta jawabannya selanjutnya. Untuk mempelajari al Qur’an guna sampai memperoleh pengetahuan dan pemahaman dengan hasil sebagaimana yang dimaksud oleh al Qur’an, yaitu huda, jalan filsafat yang menimbulkan Trilemma Bab 4 133 Munchhausen itu tidak sesuai dengan prinsip yang ditentukan oleh al Qur’an. Prinsip-prinsip yang ditetapkan di dalam al Qur’an sendiri untuk mempelajari dan memahami al Qur’an agar tercapai maksud yang dikehendaki oleh al Qur’an, dituntut mutlak untuk dipenuhi sebagai dasarnya. Prinsip-prinsip tersebut bilamana diambil padanannya dengan apa yang terdapat di dalam filsafat, dapat dikatakan sebagai ‘disiplin’ dalam mengkaji al Qur’an. Dari itu, untuk memenuhi tuntutan al Qur’an tersebut, para ulama dari masa yang lalu sampai kini tetap masih berupaya mencari suatu jalan tentang bagaimana mengkaji al Qur’an sebagaimana yang ditentukan oleh al Qur’an sendiri. 7. Andalan Utama tentang Mengetahui Manusia Dasar Kemampuan Sejak dikembangkannya filsafat epistemologi di Barat, dalam memandang pengetahuan dan ilmu pengetahuan, filsafat semakin lama semakin menjauhkan diri dari percaya kepada Dhat yang Maha Tinggi yang mengatasi manusia. Filsafat berkembang dengan hanya mengandalkan diri kepada kemampuan manusia sendiri. Demikian juga tentang pengetahuannya. Tentang itu, hanya mengandalkan pada kemampuan tahu manusia sendiri, yang sumbernya ialah pikiran yang metaphysis, atau pengalaman nyata. Dengan andalan-andalan itu, pertanyaan awal filsafat yang dikemukakan sejak Plato, menunjukkan bahwa filsafat memandang kenyataan semesta ini sebagai misteri yang mengandung teka-teki tentang apa sebenarnya semesta kenyataan ini? Dari pertanyaan itu jelas, bahwa dalam pemikiran filsa-fat disadari bahwa semesta kenyataan yang berada di sekeliling ini adalah teka-teki yang penuh dengan kegelapan bagi manusia. Di dalam sejarah Eropa Barat dinyatakan bahwa sampai abad ke XII Eropa Barat berada di dalam abad kegelapan, abad yang disebut the dark ages. 134 Landasan Epistemologi... Kegelapan tentang semesta kenyataan ini, dihadapi filsafat dengan mengandalkan hanya kepada kemampuan daya pikir manusia. Hal itu dilakukan dengan rintisan untuk memikirkannya secara radikal dan logis sistematis yang disebut jalan filsafat. Dalam kegiatan memikirkan semesta kenyataan sebagai teka-teki, diperoleh jawaban yang sifatnya berupa tebakan terhadap itu. Terhadap kegelapan tentang semesta kenyataan itu di dalam sejarah Islam, zaman sebelum datangnya Islam juga disebut sebagai zaman jahiliah, atau zaman kegelapan. Artinya bahwa semesta kenyataan ini pada masa itu adalah suatu misteri yang mengandung teka-teki yang tidak ada yang dapat memberikan penjelasan tentang clara et distincta perceptionya. Dengan datangnya Islam yang diajarkan oleh Rasulullah, kegelapan tersebut diungkap. Untuk mengungkap itu pertama-tama dituntut untuk memiliki alat yang dapat membawa terang terlebih dahulu keadaan gelap itu. Di dalam keadaan gelap, bilamana ingin tahu tentang sesuatu mengenai apa dan bagaimananya yang ada di dalam keadaan yang gelap, diajarkan bahwa sebelumnya orang harus menggunakan suatu alat yang dapat membuat keadaan gelap itu berada dalam keadaan yang terang terlebih dahulu. Di dalam permulaan surat al Baqarah, alat yang dapat membawa keadaan terang itu ialah ‘i m a n ‘ kepada Yang Maha Pencipta semesta kenyataan ini. Dengan iman orang akan dibawa kepada pengakuan bahwa semesta kenyataan ini ada yang menciptanya. Selanjutnya bahwa ciptaanNya itu ada dan berjalan menurut ketentuan dan rancanganNya sebagaimana dikehendaki olehNya. Dengan itu semesta kenyataan ini hanya dapat diketahui dan dimengerti, bila tentang itu diperoleh penjelasan dari Yang Maha Mencipta itu. Penjelasan itu hanya dapat diterima oleh manusia bila dia pertamatama beriman kepadaNya sebagai Maha Penciptanya. Pengetahuan atas dasar iman, adalah pengetahuan yang diperoleh bukan atas dasar menerka dalam kegelapan. Pengetahuan itu diperoleh dan didasarkan pada pemberitahuan dari Penciptanya sendiri. Bab 4 135 Dengan dasar itu selanjutnya oleh al Qur’an ditunjukkan syaratsyarat lain yang harus dipenuhi seseorang yang sudah berada di dalam keadaan yang ‘terang’ jiwanya untuk mengembangkan pengetahuannya selanjutnya. Syarat-syarat itu, seperti tertera di dalam permulaan surat al Baqarah, bila dikemukakan secara bebas adalah sebagai berikut: a. Bahwa dalam segala keadaan, seorang di dalam menjalani keadaannya, akan selalu tetap memerlukan petunjukNya untuk dapat selalu berada didalam jalan yang lurus yang ditentukan olehNya, b. Bahwa didalam menjalani ke-ada-annya, orang harus menjauhkan diri dari watak tamak yang materialistis, c. Bahwa semesta kenyataan ini olehNya ditentukan berada dalam suatu proses yang tiada hentinya menuju kepada bentuknya yang terakhir sebagaimana yang dikehendakiNya. Dengan prinsip-prinsip tersebut sebagai syarat dan dasar yang mutlak untuk diyakini dan diamalkan, dalam memahami semesta kenyataan diperintahkan kepada manusia untuk selalu menggunakan alat-alat kemampuan mengetahui dan memahami yaitu fikiran, akal dan hati yang ada pada manusia. Tentang fikiran dan akal, pemikiran filsafat telah banyak mengajukan pembahasan tentang pikiran. Tentang ‘hati’, mengenai yang ada hanya sangat sedikit yang menanganinya secara rinci. 8. Dinamika Kegiatan Keilmuan dan Keilmiahan Kaum Muslimin Banyak ayat-ayat al Qur’an yang memerintahkan manusia untuk memikirkan, mempergunakan akalnya, dan hatinya menghadapi semesta ciptaan Tuhan ini. Ayat-ayat semacam itu menjadi dasar dan pendorong yang kuat dalam kalangan muslimin untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Sejak pemerintahan khalifah Abbasiyah (abad ke VIII), kaum muslimin yang termasuk ahli ilmu dan ahli pikir mulai menunjukkan kegiatan mengembangkan keilmuannya tidak saja melulu dengan membaca dan menghafalkan ayat-ayat al Qur’an dan Hadist saja, akan 136 Landasan Epistemologi... tetapi mulai tampak merangkak mengarah kepada penggunaan cara berfikir yang lain karena pengaruh pemikiran keilmuan Parsi, India dan filsafat Yunani yang pada masa itu sudah pula dikenal di daerah Islam seperti di Parsi, Mesopotamia dan sebagainya. Dari filsafat Yunani yang dikenal antara lain ialah dari Plato dan Aristoteles. Kontak dengan pikiran-pikiran para ahli filsafat Yunani terjadi melalui buku-buku peninggalan filsafat yang ditulis oleh kaum filosuf Yunani kuno. Hal itu terjadi terutama mulai masa pemerintahan kekhalifahan Abassiyah berkat dorongan kuat pemerintah kekhalifahan pada masa itu. Kegiatan yang dilakukan oleh para pemikir dan para ahli ilmu dalam kalangan kaum muslimin pada masa itu membawa perkembangan baru dalam melaksanakan perintah al Qur’an dan Hadist untuk mengembangkan ilmu dan keilmiahan. Dimulai dari mempelajari filsafat Plato yang berupaya memikirkan segala sesuatu secara ontologis dengan memusatkan kepada pencarian hakikat dari segala sesuatu atas dasar idee, dan kemudian disusul dengan filsafat Aristoteles yang lebih mempergunakan jalan empiris. Tampak bahwa perhatian pengembangan ilmu dalam sementara kalangan ahli pikir dan ahli ilmu kaum muslimin pada masa itu, lebih condong kepada filsafat Aristoteles. Dalam pandangan Aristoteles filsafat dibedakan ke dalam berbagai cabang-cabang keilmuan seperti ilmu alam, ilmu biologi, ilmu kedokteran dan scbagainya. Terutama karena dorongan kebutuhan praktis pada masa itu, bidang ilmu kedokteran yang pertama-tama mendapat perhatian utama. Baru setelah itu menyusul yang lain-lainnya, termasuk filsafat. Suasana studi yang demikian menjadi lebih pesat lagi sewaktu masa pemerintahan Harun al Rasyid (abad ke VIII). Berkat dorongannya untuk menterjemahkan buku-buku fllsafat Yunani kuno kedalam bahasa Arab. Buku-buku Yunani kuno tersebut menjadi lebih mudah untuk dibaca, dipelajari dan dicerna oleh para ahli pikir dan para ahli ilmu Bab 4 137 dalam kalangan kaum muslimin pada masa itu. Hal itu membawa lebih pesatnya pengembangan keilmuan dalam kalangan masyarakat muslimin dalam rangka melaksanakan perintah al Qur’an dan Hadist untuk mengembangkan ilmu dan keilmiahan. Dengan kegiatan keilmuan yang demikian, pada masa itu mulai tampak adanya pengembangan ilmu dan keilmiahan yang lain bilamana dibandingkan dengan kegiatan berilmu dan keilmiahan pada masa-masa sebelumnya. Di dalam masa itu terjadi pengembangan ilmu dan keilmiahan melalui dua wawasan berilmu yang satu sama lain berlainan. Perbedaan wawasan tersebut menjurus pada satu fihak kepada aliran yang tetap setia menempuh jalan yang tradisionil. Pada lain fihak, sebagai aliran yang kedua, dengan terbuka menerima dan mempergunakan jalan fllsafat Yunani Kuno. Dua aliran wawasan dalam menempuh jalan keilmuan yang prinsipil berlainan dasar-dasamya itu tampak dengan menyolok pada bidang kajian yang mengenai Ilmu Kalam. Aliran yang tradisionil, yang dinamakan aliran ahli sunnah, melakukan kegiatan keilmuannya lewat jalan yang sudah lama ditempuh para ahli pikir dan ahli ilmu dan karenanya dengan kokoh dipertahankan dan dijalankan. Kalangan ini berpegang teguh kepada bunyi ajaran sunnah Rasulullah saja. Aliran yang baru, yaitu yang disebut aliran filsafat atau aliran ahli ra’yi atau juga disebut golongan Mu’tazilah, menekankan kepada penggunaan jalan filsafat. Bagi kalangan Mu’tazilah dalam menggunakan jalan filsafat mengutamakan kekuatan pikiran yang logis. Jalan itu bagi kalangan ini adalah pokok dan utama dalam kerangka mempelajari dan memahami al Qur’an dan di dalam mengembangkan ilmu dan keilmiahan dalam kerangka melaksanakan perintah al Qur’an. Pengembangan ilmu dan keilmiahan dalam awal abad ke IX, dalam kalangan ahli pikir dan ahli ilmu dalam kalangan kaum muslimin pada masa itu mulai diwarnai dengan perbedaan dalam dasar wawasan melaksanakan perintah al Qur’an dan Hadist untuk mengembangkan Landasan Epistemologi... 138 ilmu dan keilmiahan. Di dalam sejarah, perbedaan antara kedua aliran tersebut menunjukkan timbulnya pertarungan yang sengit. Pertarungan karena perbedaan dasar wawasan pendekatan ilmu dan keilmuan tentang al Qur’an antara kedua aliran tersebut, tampak seperti terjadinya suatu ‘perang tentang dasar dan methode berilmu’. Perang tersebut tidak hanya dalam arti beradu alasan. Tetapi juga sampai pada beradu kekuatan dalam politik dan fisik. Apapun keadaannya, pengembangan ilmu dan keilmiahan yang Islami yang dilakukan oleh kedua aliran tersebut dalam sejarah pemikiran ilmu dan keilmiahan dalam kalangan ahli pikir dan ahli ilmu kaum muslimin pada masa itu merupakan aliran-aliran yang menentukan pengembangan ilmu dan keilmiahan untuk masa-masa selanjutnya sampai kini. 9. Mencari Keseimbangan Adanya perbedaan prinsipil dalam dasar wawasan me-ngembangkan ilmu dan keilmiahan yang diajukan oleh kedua aliran tersebut, menimbulkan adanya upaya untuk menemukan jalan untuk menengahi kedua aliran dasar tersebut. Jalan tengah tersebut, dibangun dengan menunjukkan dan menjabarkan suatu dasar dengan melalui jalan pendekatan baru. Dasar itu bukan fikiran yang radikal semata, bukan mengikuti secara taklid semata pada apa yang dianggap sebagai sunnah Rasullullah. Dasar baru yang dikemukakan itu ialah dengan menarik ke dalam dimensi yang lebih jauh dan lebih dalam dasar-dasar yang dipertentangkan itu untuk diletakkan pada apa yang asasi bagi identitas kemanusiaan yaitu hati atau qalbu . Ulama yang menggarap dasar baru ini dengan tekun ialah al Ghazali (1058- 1111 M). Dia adalah seorang ulama yang luas pengetahuan dan pengalamannya dalam ilmu Fiqh, ilmu kalam, dan juga ilmu filsafat. Kajiannya tentang hati, olehnya tidak dimasukkan ke dalam kajian filsafat, juga tidak ke dalam ilmu fiqh atau ilmu kalam. Kajiannya tentang itu termasuk di dalam kajian yang olehnya disebutnya sebagai kajian tasawwuf. Bab 4 139 Catatan: Banyak kalangan yang berpendapat bahwa tasawwuf adalah cara melaksanakan ajaran Islam dengan jalan menjauhkan diri dari urusan duniawi. Tasawwuf dalam pandangan yang demikian adalah sama dengan ‘zuhud’ yaitu suatu gerakan semacam mystik, yang hanya mementingkan urusan hidup akherat saja. Juga tasawwuf dalam hubungannya dengan faham ini disebut pula sebagai gerakan sufi. Dalam pandangan itu, ringkasnya tasawwuf diartikan sama dengan mistik dalam Islam. Pengertian tasawwuf yang demikian memang sudah lama ada sebelum Ghazali mengajarkan ilmu tasawufnya. Dengan demikian sewaktu Ghazali memperkenalkan pengertian tasawufnya sebagai semacam teori pengetahuan, istilah tersebut masih tetap dipahami dalam arti tradisionil yang sudah mapan. Ajaran tasawuf Ghazali mengandung pengertian lain dari pengertian tasawuf yang tradisionil. Bila diperhatikan dengan kritis, pengertian tasawuf yang diajarkan Ghazali, dalam arti umumnya, berisi suatu upaya mengkaji ajaran Islam secara yang ditentukan dalam al Qur’an, Hadist, dan menurut pandangan para sahabat serta para ulama. Jalannya ialah dengan meninggalkan filsafat yang hanya mengandalkan pada daya pikir yang radikal, logis sistematis dalam menghadapi pertanyaan tentang sesuatu dalam kerangka kesemestaannya. Pendekatan melalui jalan tasawuf yang diajarkan oleh Ghazali pertama-tama ialah pendekatan dengan menggunakan potensi tahu manusia yang berada dalam dimensi jauh lebih dalam dari sekedar daya akal-pikiran yang logis saja. Pendekatan tasawuf, menempatkan akal-pikiran yang logis dalam kaitan persenyawaannya dengan sumber potensi tahu dalam dimensinya yang berada pada dataran yang sedalam-dalamnya dan mendasar sampai pada datarannya yang paling awal yang ada didalam diri seorang manusia yaitu hati atau qalbu. Menurut pandangan Ghazali, segala pengetahuan pada dasarnya adalah berkat bekerjanya ‘hati’. Secara ringkas, hal itu dapat dijelaskan dalam struktur dan sistimnya sebagai berikut: Yang paling dasar di 140 Landasan Epistemologi... dalam kemampuan tahu manusia ialah ‘hati’. Dasar ini yang merupakan kemampuan melihat awal dan asasi. Seterusnya itu yang membuat lainlain alat kelengkapan tahu dapat berfungsi. Di atas hati, diantara kelengkapan tahu yang penting ialah akal-fikiran. Ini adalah pengolah bahan-bahan yang menjadi objek tahu yang ditangkap oleh panca indera dan alat penangkap batiniah yang ada di dalam jiwa manusia. Struktur piranti tahu tersebut, selanjutnya oleh Ghazali dijelaskan sistimnya sebagai berikut: 1) Mulanya berkat lintasan yang tertangkap oleh pancaindera atau lainnya, melalui proses dalam pikiran dan akal, hasil tangkapan itu menjadi suatu bahan untuk dapatnya dicerna oleh hati yang mempunyai kekuatan ilmu, hikmat, kalimat dan suatu kekuatan hati yang dinamakan nafsu. Dengan itu semua, hati mampu membentuk bahan-bahan itu menjadi pengertian dan pengetahuan. 2) Dengan pengertian dan pengetahuan itu terbentuk gambaran dalam hati berupa sesuatu yang menyerupai wujud sejati dari sesuatu yang tergambar dalam hati itu. 3) Dengan gambar pada hati itu terbentuk apa yang disebut pengetahuan tentang sesuatu yang bersangkutan. 4) Sebagai pengetahuan, itu kemudian mengendap ke dalam hati menjadi apa yang disebut diketahui oleh hati. 5) Dengan apa yang telah merupakan diketahui oleh hati kemudian terbentuk suatu pandangan atau penglihatan dalam hati. 6) Pada hati ada suatu kekuatan khusus yang berfungsi melakukan kegiatan menggores apa yang telah diketahui oleh hati. Dengan itu, apa yang merupakan hal yang diketahui oleh hati menjadi tetap berbekas dihati. Sehingga apa sudah diketahui itu tidak hilang begitu saja. Kekuatan yang menggoreskan dalam hati itu disebut Qalam. 7) Goresan pandangan atau penglihatan hati itu dipantulkan oleh hati keluar. Itu segera ditangkap oleh akal fikiran lagi. Pantulan yang keluar dari hati itu diolah lagi oleh akal fikiran. Setelah itu dipancarkan keluar menjadi apa yang disebut ‘i1mu’. Ilmu dengan demikian dalam pandangan Ghazali tidak lain adalah pandangan atau penglihatan hati, yang setelah melalui pengolahan akalfikiran, menjadi gambaran dalam jiwa manusia tentang sesuatu yang menyerupai sungguh wujud sejati dari sesuatu dan yang sudah tergores di dalam hati. Bab 4 141 Catatan: Di dalam al Qur’an surat al Baqarah. IImu yang diberikan oleh Allah s.w.t. kepada manusia, i.c. Adam, tidak saja hanya ilmu itu saja, akan tetapi seketika pula hikmatnya yaitu suatu jenis kemampuan mengetahui yang termasuk di dalam lingkungan ma’rifatnya. Setelah itu disusul dengan pemberian jenis pengetahuan lain yang di dalam surat al Baqarah dinamakan ‘kalimat’. Masih pula di dalam surat tersebut disebutkan, bahwa bagi mereka yang beriman, akan diberi tambahan satu jenis pengetahuan lagi yaitu yang dinamakan ‘huda ‘. Memperhatikan ayat-ayat di dalam surat tersebut, jadinya ilmu saja, dalam kerangka artinya yang ada di dalam ayat-ayat surat tersebut, tidak cukup untuk bekal manusia menjalani hidupnya diatas bumi. Selain itu, masih diperlukan ada jenis pengetahuan lain yaitu hikmat atau ma’rifatnya dan kalimat atau syariatnya. Jika diikuti pandangan Ghazaii tersebut, hati adalah yang menjadi pusat dan sumber dalam menjadikan segala apa yang telah tertangkap oleh pancaindera atau lain alat kejiwaan, dengan melalui pengolahan akalfikiran menjadi pengetahuan pada hati. Dari wujudnya sebagai pengetahuan yang tergores pada hati, kemudian itu menjadi suatu pandangan atau penglihatan hati. Itu yang dipantulkan kembali oleh hati keluar untuk diolah oleh akal-fikiran lagi menjadi ilmu. Tentang penjelasan lebih lanjut dari Ghazaii mengenai ilmu dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Memantulkan sesuatu goresan yang ada pada sesuatu permukaan hati, adalah suatu hal yang berlangsung tidak mulus. Banyak persyaratan yang menjadikan pantulan itu menjadi bermacammacam. Di antaranya ialah bahwa ada kemungkinan permukaan hati itu berada didalam keadaan yang sedemikian bersih dan licin, sehingga kilauannya memungkinkan memberikan pantulan dari goresan yang ada pada permukaan hati itu berada dalam keadaan yang terang, bersih dan murni.Itu berarti bahwa keadaan hatilah yang menentukan bagaimana hasil pantulan pandangan hati untuk menjadi ilmu yang akan diperoleh seseorang. 2) Keadaan hati menurut Ghazali dapat bermacam-macam. 3) Hati dapat dalam keadaan bersih, tetapi juga dapat dalam keadaan kotor. Juga pada hati ada dasar yang berlainan antara seseorang 142 Landasan Epistemologi... dengan orang lainnya. Dari itu pantulan pandangan yang dipancarkan oleh hati dan kemudian menjadi ilmu dapat bermacam-macam hasilnya. 4) Dalam hubungannya dengan itu, ada lagi tentang keadaan hati yaitu ada hati yang diisi dan dipenuhi ‘iman’ dan ada hati yang tidak berisi sama sekali, artinya kosong dari ‘iman’. Perbedaan tentang keadaan hati seseorang itu yang memberikan pancaran pandangan yang kemudian menjadi ilmu yang masing-masing dapat berbeda-beda dalam hal: dimensinya, dalam cakrawala yang dapat dijangkaunya, dalam bentuk dan wujud yang dipancarkannya, dalam ketepatan dan kebersihan serta kemurniannya, dalam sifatnya, ringkasnya dalam kwalitasnya. Di sini letak keterangannya mengapa ilmu yang ada dan dibawakan oleh seseorang berlainan satu dari yang lain. Khusus mengenai hati dan iman Iman tidak terletak di dalam alam fikiran. Juga tidak di dalam alam akal. Letak iman ialah jauh di dalam dasar lubuk hati. Lubuk hati yang diisi dan dipenuhi dengan iman, berarti lubuk hati yang berada dalam keadaan yang sudah diterangi. Pada hati yang demikian berarti ada alat penerangnya. Dengan itu hati berada di dalam keadaan yang diterangi. Dalam keadaan itu hati akan mempunyai daya memantulkan pandangan yang berlainan dengan hati yang dalam lubuk hatinya tidak ada kandungan iman. Catatan: Iman menurut hemat saya adalah istilah khusus dari suatu jenis dasar dari lubuk hati. Istilah umumnya ialah apa yang disebut: percaya. Percaya terdiri dari beberapa macam. Pertama ialah percaya yang alami yaitu percaya yang isinya suatu pendirian yang bagaimana saja isinya dan yang sudah kokoh tak tergoyahkan tertanam didalamnya. Kedua ialah percaya yang isinya ialah pengakuan yang kokoh tak tergoyahkan tentang adanya Yang Gaib, Maha Tunggal, Maha Pencipta sekalian alam dan karenanya Yang Maha Mengetahui. Percaya jenis ini yang disebut iman. Ketiga ialah percaya yang isinya tidak mantap dan bergerak antara yang pertama dan yang kedua. Percaya dalam kwalitas ini adalah percaya yang dinamakan munafiq. Bab 4 143 Percaya lokasinya ada didalam dasar lubuk hati. Kedudukannya dalam hal mengetahui ialah, diantara: alam tahu dan alam tidak tahu. Dalam filsafat epistemologi Barat, yang mengandalkan diri dalam hal ilmu pada akal fikiran ataupun pada empiri, itu berarti bahwa hatinya kosong dari ‘iman’ kepada Dhat yang Mencipta semesta ini. Dengan keadaan itu, hatinya berada didalam keadaan yang gelap. Keadaan itu yang memberikan perbedaan hasil ilmu yang diperoleh melalui jalan tasawwuf dan ilmu yang diperoleh melalui jalan filsafat. Dari gambaran tentang sistim dari proses pembentukan pengetahuan ke dalam hati sampai terbentuknya pengetahuan hati menjadi ilmu, dalam pandangan Ghozali tampak bahwa proses untuk sampai kepada hati guna menjadi pengetahuan hati maupun proses yang berawal dari pengetahuan yang ada didalam hati untuk menjadi ilmu, masing-masing memang harus melalui akal-fikiran terlebih dahulu untuk diolah. Proses yang pertama ialah dari kerja tangkapan pancaindera atau lain alat kejiwaan yang menjadi masukan bagi alam pikiran. Bahan bahan semacam itu, pertama-tama melalui akal-fikiran, diproses untuk dapat dituangkan kedalam hati untuk menjadi pengetahuan. Proses yang kedua ialah dari hati bahan masukan dari luar yang sudah diolah menjadi pengetahuan, kemudian menjadi pandangan. Dalam bentuknya sebagai pandangan kemudian masuk ke dalam akal-fikiran. Di sini pandangan itu diproses lagi menjadi ilmu. Dalam kedua macam proses yang dikerjakan oleh akal-fikiran, ringkasnya di sini untuk mudahnya kita sebut saja ‘proses prapengetahuan’ dan ‘proses pasca-pengetahuan’ peran akal-fikiran dalam mengolahnya adalah untuk menjadikan bahan-bahan yang bersangkutan siap menjadi bahan yang mencapai wujud yang sesuai dengan yang diperlukan untuk tujuan yang dimaksudkan dalam tahap proses yang bersangkutan. Jelasnya proses pertama yaitu proses pra-pengetahuan yang dikerjakan oleh akal-fikiran adalah untuk menjadikan bahan hasil tangkapan pancaindera atau alat lainnya dari jiwa itu dapat dicerna oleh hati untuk diolah menjadi pengetahuan. Landasan Epistemologi... 144 Proses kedua yaitu proses paska-pengetahuan dalam akal-fikiran adalah untuk dapatnya pandangan hati itu terpancar keluar dalam wujudnya sebagai ilmu. Dalam kedua macam proses tersebut, akalfikiran dalam mengolah bahan-bahannya tidak menggunakan nilai susila atau menurut nilai moral. Bagi akal-fikiran yang menjadi tugasnya adalah menyiapkan bahan-bahan yang bersangkutan untuk dapat siap mencapai keadaan yang sesuai dengan apa yang dimaksud oleh tahap proses pengolahan yang bersangkutan. Setelah hasil proses pasca-pengetahuan selesai dilaku-kan oleh akalfikiran, baru terpancar pandangan pengetahuan hati itu dalam bentuknya sebagai ilmu. Sehubungan ilmu tidak lain dari pada rasionalisasi pandangan hati, di dalam pernyataannya sebagai ilmu di dalam alam syahadat ditegaskan sekaligus bahwa ilmu hanya pernyataan dari kandungan pengetahuan hati. Karenanya ilmu yang dipancarkan tersebut juga diberi sebutan sebagai ‘ilmu-pengetahuan’. Dalam hal ini kata ‘pengetahuan’ menunjuk kepada isi kandungan pengetahuan yang ada di dalam hati. Bagan Ilmu Pengetahuan Menurut Jalan Tasawwuf Alam Nyata Alam Gaib Panca Indera Alat Batin Pikiran - A Logis - Logis Akal Hati - Ilmu, Hikmah, Kalimatt (Penangkap) - Syahwat (Kemauan) -Kekuasaan (Akal) Percaya Iman Ilmu Pengetahuan Pikiran - Logis - Sistematis Akal Pandangan hati / Penglihatan Hati Pengetahuan Hati Bab 4 145 10. Ilmu dan Keilmiahan dalam Wawasan Ke-Islaman Sebelum dimulai pembahasan persoalan tersebut, perlu dijelaskan arti ‘wawasan ke-Islaman’. Kata majemuk tersebut menunjukkan, bahwa apa yang dikemukakan dengan istilah itu, bukan sama dengan ajaran Islam. Itu hanya merupakan pendapat sementara kalangan muslimin tentang ilmu dan keilmiahan, yang pribadi dan jiwanya didasari persyaratan sebagai muttaqin dalam membaca dan memahami al Qur’an. Dengan demikian wawasan di dalamnya mengandung unsur pendapat subjektip tentang bagaimana ilmu dan keilmiahan menurut penglihatannya yang dasar dan sumbernya diarhbil dan ajaran Islam yang ditangkap dan difahaminya secara subjektip. Unsur subjektif dalam suatu wawasan, menunjukkan tidak dapatnya wawasan itu sama dengan apa yang ada di dalam ajaran Islam yang sesungguhnya. Dengan sebutan ‘wawasan ke-Islaman’, unsur subjektivitas pendapat orang yang bersangkutan menjadi menonjol. Di dalam wawasan yang bersifat demikian, risiko kurang sesuai sepenuhnya dengan ajaran al Qur’an dan Sunnah Rasulullah, akan selalu ada. Dengan itu suatu wawasan akan menjadi tetap bersifat keilmuan. Dengan sifat itu, wawasan selalu merupakan sesuatu pendapat yang tunduk pada suatu koreksi dan kritik. Dengan itu, koreksi dan kritik ilmiah terhadap wawasan menjadi tidak tertuju kepada dalil al Qur’an atau Hadist yang dikupas. Kritik akan tertuju kepada pendapat subjektip dan pemikir yang bersangkutan terhadap tafsirannya tentang ayat al Qur’an atau sunnah Rasul yang dimaksud. Tentang wawasan yang akan dipilih di sini, ialah wawasan yang dasarnya bukan pemikiran filsafat. Yang menjadi pilihan disini ialah wawasan yang bernafaskan ajaran Islam, sekali lagi bukan dalam arti ajaran Islam. Dan itu pilihan terhadap wawasan di sini adalah merupakan pilihan tentang suatu pendapat yang merupakan tafsiran dan ajaran Islam yang diajukan oleh seorang muslim. Dalam wawasan yang demikian, yang menjadi titik tolak bukan mengandalkan kepada daya pikir manusia. Yang menjadi andalannya 146 Landasan Epistemologi... ialah keimanan pada Ilahi dan wahyuNya yang diturunkan kepada manusia melalui RasulNya. Itu yang mengisi hatinya dan yang dijadikan sebagai sumber wawasan pengetahuan-pandangannya tentang semesta kenyataan ini. Wawasan yang dipilih dalam uraian di sini di dalam menghadapi pertanyaan ilmu dan keilmiahan, bukan wawasan yang berdasar pada filsafat, tetapi wawasan yang diperoleh melalui jalan tasawwuf. Pendekatan melalui jalan ini, kiranya perlu didahului suatu uraian ringkas tentang genealogi ilmu menurut wawasan tasawuf sebagaimana diutarakan oleh Ghazali. Secara bebas dan ringkas itu adalah sebagai berikut: a. Tentang arti ilmu. Di dalam al Qur’an maupun di dalam Hadist, sejauh yang kita ketahui, tidak ada definisi tentang apa ilmu itu. Memang banyak Hadist yang berhubungan dengan ilmu dan keilmiahan. Akan tetapi sejauh ini yang kita ketahui, tidak ada yang dapat dipandang sebagai definisi tentang apa yang dimaksud dengan ilmu. Bilamana diperhatikan ayatayat al Qur’an dalam surat al Baqarah yang disebut diatas, Ilmu, dalam ayat-ayat tersebut tampak bahwa yang dimaksud dengan istilah ilmu adalah dalam pengertiannya yang terbatas artinya. Dalam ayat yang bersangkutan, ilmu dihubungkan dengan kemampuan manusia untuk menentukan dan menyebut nama dan segala sesuatu yang ada di dalam alam kenya-taan. Selain itu termasuk pula kemampuan memperbedakan sesuatu dari sesuatu yang lain. Kemampuan yang demikian adalah daya kerja fikir manusia. Di dalam surat al-Baqarah, juga dikemukakan tentang kemampuan tahu manusia yang lain, yaitu pengetahuan tentang hikmat yaitu daya bekerjanya akal yang membawa manusia kepada pengetahuan tentang ma’rifat. Selanjutnya yang terakhir disebut itu juga meliputi kemampuan yang ada pada manusia tentang nilai-nilai. Pengetahuan tentang ini dapat kita namakan sebagai pengetahuan tentang syariatnya. Kemampuan tahu ini adalah kemampuan dari daya kerjanya hati. Dari bunyi ayat-ayat yang kita maksud di atas dapat disimpulkan, bahwa pengetahuan manusia terdiri atas tiga bagian yaitu Bab 4 147 pertama ilmu, kedua ialah ma’rifat dan ketiga ialah syariat. Ghazali di dalam membahas soal ajaran Islam dan ilmu selalu mengkaitkan ilmu dan ma’rifatnya. Hal ini berarti bahwa bagi Ghazali di dalam memahami ajaran Islam tentang pengetahuan, pada manusia selalu ada kemampuan yang menentukan jenis dan perbedaannya satu dengan lainnya. Selain itu sekaligus pula pada ilmu, ada pula kemampuan untuk mengetahui sifat-sifat yang ada pada sesuatu yang bersangkutan baik secara tersendiri maupun bila itu dalam hubungannya dengan lain-lainnya yang terdapat didalam cakupan kemampuan tahu melalui pancaindera dan alat lain yang ada didalam jiwa. Keseluruhan daya tahu yang meliputi ketiga hal tersebut di dalam sebutan sehari-hari, maupun di dalam kalangan ilmu pengetahuan sendiri, sering disingkat dengan sebutan ilmu saja. Sering juga diberi tambahan kata pengetahuan, sehingga menjadi sebutan ilmu pengetahuan. Kemampuan berilmu-pengetahuan semacam itu di dalam ajaran Islam, adalah berkat pemberian Allah s.w.t. Ketiga jenis kemampuan berilmu tersebut ada dan dimiliki setiap orang dalam takaran yang berlain-lainan. Itu tergantung pada usaha masing-masing orang yang bersangkutan untuk mengembangkannya. b. Tentang wawasan ilmu dan keilmiahan keIslaman. Bagaimana wawasan ilmu dan keilmiahan yang bersumber pada ayat-ayat al Qur’an dan Hadist, dari kalangan pemikir dan ahli ilmu kaum muslimin, tampak adanya perkembangan yang bertahap. Tahap-tahap perkembangan yang menonjol ialah : 1) Tahap pertama yaitu pada masa Rasulullah masih hidup, 2) Tahap kedua yaitu pada masa masih hidupnya para sahabat setelah Rasulullah wafat, 3) Tahap ketiga yaitu abad VII, yaitu masa masih hidupnya para tabi’in, 4) Tahap keempat yaitu abad VIII, tahap mulai adanya perubahan awal dalam pendekatan mengkaji ajaran Islam oleh para ahli pikir dan ahli ilmu dalam kalangan kaum muslimin karena masuknya pengaruh dasar pemikiran dari India dan Parsi yang magis-mystis pada satu fihak dan atas dasar yang logis filsafat Yunani kuno pada fihak lain, 148 Landasan Epistemologi... 5) Tahap kelima yaitu abad IX-XII sebagai tahap pengembangan lebih lanjut dari jalan pendekatan mengkaji ajaran Islam secara plural, 6) Tahap keenam yaitu abad XIII sampai kini sebagai tahap kelanjutan pengembangan dari tahap kelima diatas. Di bawah ini hal itu sekali lagi akan diajukan penjelasannya secara ringkas. Ulangan penjelasan ini dilakukan untuk memudahkan pembahasannya. 1) Dalam tahap pertama, persoalan tentang ilmu dan keilmiahan dalam mempelajari ajaran Islam, tidak mengandung persoalan yang menyolok. Pada waktu itu segala persoalan mengenai ajaran dan pelaksanaan Islam masih berpusat pada apa diri Rasulullah secara langsung. 2) Dalam tahap kedua, tugas membina ajaran dan pelaksanaan ajaran Islam berada pada para sahabat. Di dalam masa ini, satu hal yang penting untuk keilmuan ialah: pertama adanya tafsiran yang berbeda diantara kalangan para sahabat dan pengikutnya masing-masing; kedua ialah adanya kodifikasi al Qur’an. Dengan adanya kodifikasi al-Qur’an bahan dasar dan pokok ajaran Islam tersimpan dan terjamin otentisitasnya sampai kini. Sejak tahap ini, keilmuan ke Islaman mendapat tantangan. Tantangan pertama ialah bagaimana jawaban atas perbedaan pendapat antara sementara pengikut para sahabat tentang pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh sahabat yang bersangkutan. Kedua ialah ilmu dan keilmiahan ke Islaman memperoleh bahan yang otentik dan pasti untuk dengan mempergunakan sunnah Rasulullah dan bimbingan para sahabat sebagai tambahan, mengembangkan pemahaman tentang ajaran Islam. Wawasan keilmuan dalam tahap ini masih sangat kuat terikat pada al Qur’an dan Sunnah Rasulullah di bawah bimbingan para sahabat. 3) Dalam tahap ketiga, perhatian baru tentang keilmuan mengenai ajaran Islam mulai tumbuh dengan adanya upaya untuk membukukan sunnah Rasulullah dalam kerangka semangat mengkaji dan melaksanakan ajaran Islam yang ada di dalam al Qur’an dengan secara tepat. Hal itu terjadi berkat kuatnya wawasan ilmu dan keilmiahan hanya harus dilakukan melalui jalan taklid terhadap sunnah Rasulullah. Dalam tahap ini menjadi lebih jelas terbentuknya dasardasar untuk mengkaji ajaran Islam yang ada didalam al Qur’an atas dasar taklid pada sunnah Rasulullah. Ini merupakan tahap awal dari lahirnya aliran berilmu didalam kalangan muslimin tentang apa yang dikemudian hari disebut aliran Ahlussunah. Bab 4 149 4) Tahap keempat ialah tahap, dimana bahan-bahan mengenai ajaran Islam yaitu al Qur’an dan sunnah Rasulullah sudah tersedia dalam bentuk tertulis. Dengan itu bahan-bahan tersebut lebih mudah untuk diperoleh guna dipelajari isinya. Dalam keadaan yang demikian mulai dikenal terutama karya filsafat Yunani kuno didalam kalangan para ulama. Disamping itu juga ada kalangan yang lebih memilih aliran berilmu menurut faham Parsi dan India. Dengan masuknya tulisantulisan filsafat Yunani kuno itu mulai masuk pula pengaruh filsafat didalam perkembangan ilmu dan keilmiahan dalam kalangan para ahli pikir dan ahli ilmu dalam kalangan kaum muslimin. Pengaruh tersebut tampak terutama dalam menentukan jalan pendekatan ilmu dan keilmiahan tentang Islam secara rasionil. Pendekatan ilmu dan keilmiahan terhadap ajaran Islam karena pengaruh itu menjadi ada yang lain dari apa yang ditempuh pada masa yang sudah lalu. Jalan taklid pada sunnah Rasulullah, dengan itu memperoleh tandingan yang kuat yaitu jalan filsafat. Jalan ini mempergunakan pemikiran yang radikal, logis sistematis. Dari itu, aliran baru ini disebut sebagai aliran rasionil, aliran ra’y. Aliran yang tradisionil, sebagai aliran yang pertama, dasarnya adalah taklid kepada sunnah Rasul. Aliran ini terkenal dengan sebutan aliran ahlussunnah wal jamaah. Aliran yang kedua, sebagai aliran filsafat, disebut aliran mu’tazilah. Dengan adanya dua wawasan ilmu dan keilmiahan dalam mempelajari ajaran Islam yang ada didalam ah Qur’an dan Hadist itu tampak bahwa dalam tahap ini bersemi kehidupan ilmiah dalam ilmu kelslaman yang lebih nyata. 5) Tahap kelima ialah tahap kematangan perkembangan kehidupan dari pertentangan dua wawasan ilmu dan keilmiahan ke Islaman di atas. Pertarungan antara kedua aliran itu menimbulkan suatu wawasan yang tampaknya sebagai memadukan kedua wawasan tersebut. Perpaduan itu dirintis oleh seorang ulama besar yaitu Ghazali. Dalam pertentangan kedua aliran wawasan itu, Ghazali, sekalipun tetap menjunjung tinggi aliran ahlussunnah wal jamaah, aliran filsafat yang dipertahankan oleh kalangan Mu’tazilah sekalipun terselubung tampak juga mendapat perhatiannya. Selain itu, dalam upayanya tersebut tampak pula masih adanya jalan pikiran yang dilatarbelakangi oleh model Parsi dan India yang magis-mystis. Aliran tersebut didudukannya pada tempat yang setepatnya menurut petunjuk al Qur’an dan Hadist, pendapat para sahabat dan para ulama yang besar. 150 Landasan Epistemologi... Dalam upayanya itu, apa yang dilakukannya ialah dengan memperkenalkan jalan yang disebutnya jalan tasawuf. Ilmu ini mengutamakan jalan mendekati al Qur’ an dan Hadist Rasulullah melalui apa yang dinamakannya hati atau qalbu. Dalam mengajukan wawasan keilmuan yang dinamakan wawasan tasawuf, Ghazali pertama-tama tidak mendasarkan diri pada jalan pemikiran filsafat. Penglihatan secara tasawuf yang diajukannya itu dasar dan sumbernya ialah jiwa yang taqwa, yaitu dasar wawasan dari seorang yang muttaqin. Wawasan itu olehnya ditegaskan bahwa pertama-tama dasarnya ialah dimulai dengan iman kepada Allah s.w.t. Pencipta semesta alam, Rabbil alamin. Dalam semesta alam itu dimaksudkannya termasuk pula ilmu dan keilmiahan. Dibawah ini akan dikemukakan sekali lagi secara lintasan wawasannya itu dengan beberapa tambahannya yang diperlukan. Wawasan ke-lslaman tentang ilmu dan keilmiahan yang demikian menurut Ghazali, tidak mengandalkan kepada kemampuan kekuatan akal manusia yang metaphysis atau pengalaman manusia yaitu pendirianpendirian yang dianut dalam filsafat epistemologi. Ilmu dan keilmiahan adalah potensi yang ada pada manusia sebagai pemberian Allah s.w.t. bIlmu dan keilmiahan yang dianugerahkan oleh Allah s.w.t. itu pangkalnya dan pusatnya diletakkan di dalam hati manusia. Akal fikiran adalah sebagai penangkap-mula dan pengolah bahan masukan dari luar untuk dapat masuk di dalam jiwa manusia. Kemudian bahan itu diteruskan kepada hati. Di situ bahan masukan dari akal-fikiran itu diolah oleh hati menjadi pengetahuan hati. Pengetahuan yang demikian kemudian menjadi penglihatan atau pandangan hati. Dari hati itu diteruskan ke akal-fikiran lagi untuk diolah menjadi ilmu. Demikian itu ringkasnya wawasan tentang ilmu dan keilmia-han menurut jalan tasawuf. Bila wawasan ilmu dan keilmiahan atas dasar jalan tasawuf ujudnya sebagai ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut: 1) Ilmu tidak sama dengan penglihatan hati. Pembentukan penglihatan hati harus dibimbing oleh wahyu Ilahi. Setelah melalui suatu proses pengolahan oleh akal-fikiran baru menjadi ilmu. Bab 4 151 2) Wawasan yang demikian yang dipergunakan Ghazali untuk mewadahi ilmu dan keilmiahan beserta perkembangannya. Wawasan itu di dalam sejarah pemikiran ilmu dan keilmiahan ke-Islaman temyata merupakan langkah keilmuan yang berada dalam skala sangat luas, melampaui alam pikir dan alam akal. Catatan: Gerakan mengkaji Islam yang demikian itu kini berhadapan dengan suatu usaha mengkaji Islam yang sudah dilakukan secara mantap dan telah lama berkembang yang mulanya digerakkan oleh kalangan para ahli yang tidak mau menerima Islam sebagai petunjuk Ilahi. Kalangan itu ialah kalangan keilmuan yang dasarnya ialah filsafat Barat. Pengkajiannya itu disebut dengan nama Islamologi. Kajian tentang Islam ini, berlangsung terutama di negeri yang tidak memeluk Islam dan tidak menerima al Qur’an sebagai petunjuk. Kajian tersebut berbeda-beda arah perhatiannya. Ada yang mengarah kepada kajian mengenai Islam sebagai doktrin. Ada pula yang mengisi acara kajiannya dengan kajian tentang masyarakat dan budaya kaum muslimin. Dalam hal kajian mengenai Islam yang dihubungkan dengan politik, terhadap itu ada sebutan khusus bagi para pakamya dalam bahasa Inggris yaitu yang disebut Is1amist. 11. Penutup Pertanyaan bagaimana wawasan ke-Islaman tentang ilmu dan keilmiahan, dari uraian di atas ditunjukkan bahwa itu adalah pertanyaan yang di dalam sejarah perkembangan, jawabannya merupakan pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Dalam sejarah perkembangan tentang wawasan itu, ditunjukkan bahwa diantara wawasan yang dapat meliput secara menyeluruh segala jenis ilmu dan keilmiahan yang ada, menurut hemat saya, hanyalah wawasan yang dikemukakan oleh Ghazali dalam abad ke XI Masehi. Wawasan Ghazali itu memperoleh kemantapan sampai kira-kira abad ke XII. Di dalam abad ke XIII wawasan tersebut mengalami krisis. Wawasan ilmu dan keilmiahan ke-lslaman sejak itu mulai terpecah kembali antara ahlussunnah wal jamaah sebelum Ghazali dan wawasan ahli ra’y. Selain itu juga wawasan tentang ilmu dan keilmiahan kembali menjadi menyempit. Wawasan Ilmu dan keilmiahan ke-Islaman mulai 152 Landasan Epistemologi... membatasi diri pada hal-hal yang mengenai ilmu-ilmu yang khusus mengenai tafsir al Qur’an, ilmu Hadist, ilmu kalam, ilmu fiqh, ilmu bahasa Arab. Wawasan yang demikian menempatkan ilmu-ilmu yang termasuk di dalam lingkungan ‘aqliyah’ yang menjadi perhatian ilmu-ilmu pengetahuan modern sampai dewasa ini menjadi terkesampingkan. Di dalam abad ke XIX, ada lagi rintisan dari Muhammad Abduh untuk menemukan synthesa antara wawasan-wawasan yang berseberangan tersebut dalam mengembangkan ilmu dan keilmiahan ke-Islaman, terutama di dalam bidang ilmu kalam. Setelah itu dalam abad ke XX Mahmud Syaltut, rektor universitas al Azhar, tercatat sebagai tokoh pemikir dan organisator yang mendukung wawasan yang luas tentang ilmu dan keilmiahan keIslaman. Itu dibuktikan antara lain dengan mengembangkan universitas al Azhar dengan menambah fakultas-fakultas baru yang menangani ilmu-ilmu yang berada di luar fakultas tradisionil yang hanya menangani studi tentang Islam dalam arti studi agama. Di dalam tahun 1990 tampak adanya usaha rintisan pemikiran tentang pemahaman al Qur’an yang berusaha mengikuti pandanganpandangan baru di dalam ilmu bahasa untuk menjawab tantangan kemajuan ilmu pengetahuan. Dalam hubungannya dengan ini, pemikiran itu difokuskan pada bagaimana melakukan kajian tentang al Qur’an. Kajian baru ini dirintis antara lain oleh Nasr Abu Zaid, yang mengemukakan pandangannya di dalam rangka studinya tentang “Konsep tentang text: suatu studi di dalam ilmu pengetahuan tentang al Qur’an”. Diajukan olehnya persoalan tentang textualitas dari al Qur’an. Dalam hubungannya dengan pandangan itu terkait persoalan mengenai usaha mengkaji memahami isi al Qur’an. Pemikiran yang dikemukakan itu kini dikenal sebagai pemikiran isi al Qur’an sebagai ‘text yang dalam kontext’. Tampaknya pemikiran ini dibawa pertama-tama oleh adanya persoalan pengaruh perkembangan dalam ilmu bahasa yang juga Bab 4 153 mempengaruhi studi bahasa Arab. Hal itu terutama terkait pada pemberian arti terhadap istilah ‘nass’. Dan kedua talah terkait pada pertanyaan yang sudah lama tentang al Qur’an yaitu tentang apakah al Qur’an itu qadim ataukah Hadist. Pandangan terhadap al Qur’an dalam persoalan sebagai ‘text yang dalam kontext’ tersebut, tidak terlepas dari kritik yang tajam dari kalangan para pakarnya. Salah seorang diantaranya ialah seorang guru besar dari Universitas al Azhar yaitu Muhammad Abu Musa. Apapun pertanyaannya di dalam perkembangan baru ini, wawasan ilmu dan keilmiahan ke-Islaman tampak masih tetap kembali berada di dalam bidang ilmu dan keilmiahan yang sempit. Kerangka Ghazali tentang ilmu dan keilmiahan ke-Islaman atas dasar pendekatan tasawufnya, menurut hemat saya adalah kerangka yang dapat mewadahi secara memuaskan ilmu dan keilmiahan seluasluasnya. Atas dasar pertimbangan itu, dalam meninjau “ilmu dan Ilmiah Modern dan Dasar Filsafatnya” dalam rangka wawasan ke-Islaman, kerangka tersebut akan dipakai guna menunjukkan dimana dan sampai dimana ilmu dan keilmiahan modern dan dasar Filsafatnya itu “jauhnya bilamana dibandingkan dengan wawasan ke-Islaman menurut jalan tasawuf tersebut”. Di dalam kalangan ahli tafsir, ada pendapat bahwa keseluruhan isi al-Qur’an memuat petunjuk yang dapat dibagi dalam tiga pokok bidang persoalan, yaitu: a. Bidang aqidah, b. Bidang syari’at c. Bidang sejarah. Bilamana diperhatikan secara lebih seksama, masih dapat ditambahkan lagi adanya petunjuk yang berkenaan dengan: d. Bidang filsafat e. Bidang ilmiah Dengan mengikuti kerangka pengetahuan menurut jalan tasawuf dari Ghazali, kelima bidang golongan petunjuk yang ada di dalam al- 154 Landasan Epistemologi... Qur’an itu dengan cepat dapat ditunjukkan dimana dan bagaimananya tempat masing-masing bidang golongan persoalan itu di dalam kerangka tersebut. Sudah barang tentu sebagai suatu wawasan, tinjauan yang demikian dengan sendirinya mengandung unsur-unsur pandangan yang sifatnya subjektip. Karenanya dengan sendirinya itu tetap memerlukan suatu tandingan pemikiran yang kritis.—ooo—- C. P r i n s i p - P r i n s i p E p i s t e m o l o g i t e n t a n g Pengembangan Ilmu Pengetahuan di Dalam Al Qur’an Oleh M.Syamsudin Untuk mengetahui ajaran Islam yang berkaitan atau memberikan pesan dan penjelasan tentang dasar-dasar pengembangan ilmu pengetahuan, pertama-tama yang harus dipahami dengan mantap adalah konsepsi Al-quran tentang alam raya ini (kosmologi). Sebab dari sinilah sebenarnya munculnya filsafat ilmu dalam perspektif ajaran Islam. Di dalam al-Qur’an, menurut Mahdi Ghulyani terdapat lebih dari 750 ayat yang menunjuk kepada fenomena alam. Hampir seluruh ayat ini memerintahkan kepada manusia untuk mempelajari kitab (hal-hal yang berhubungan dengan) penciptaan dan merenungkan isinya.1 Sepanjang ayat-ayat yang dijelasakan al-Qur’an itu dapat dipahami bahwa Allah menciptakan alam raya ini dalam eksistensinya yang haq, yakni benar, nyata dan baik. Yaitu bahwa Allah menciptakan alam semesta ini dengan haq (bilhaq, lihat: QS.Az-Zumar (39): 5). Alam tidak diciptakan Tuhan secara main-main (la’ab, lihat: QS.Al-Anbiya (21: 6) dan tidak pula secara palsu (bathil, lihat: QS.Shod (38): 27). Sebagai wujud yang benar (haq) maka alam raya ini mempunyai wujud yang nyata (riil), objektif dan berjalan mengikuti hukum-hukum yang tetap dan pasti (mengikuti sunnah dan taqdir-Nya). Sebagai ciptaan dari sebaik-baik Maha Pencipta, maka alam raya ini mengandung 1 Mahdi Ghulsyani. 1994. Filsafat -Sains Menurut Alquran. Bandung: Mizan.Hlm. 78 Bab 4 155 kebaikan pada dirinya sendiri dan teratur secara harmonis (lihat: QS. Al-An’am (6):73; Al-Mukminun (23):14). Nilai ini sengaja diciptakan Tuhan untuk manusia bagi keperluan perkembangan peradabannya (lihat: QS.Luqman (31): 20). Oleh karena itu alam bagi manusia dapat dan harus dijadikan objek penyelidikan guna dimengerti hukum-hukum Tuhan yang berlaku di dalamnya. Kemudian manusia harus memanfaatkan alam sesuai dengan hukum-hukumnya itu (lihat: QS. Yunus (10): 101). Keharmonisan alam itu adalah sejalan dengan serta disebabkan oleh adanya hukum-hukum yang menguasai alam, yang hukum-hukum itu ditaqdirkan Allah demikian, yakni dibuat pasti (yakni makna asal perkataan taqdir). Dalam hal ini sepadan dengan penggunaan kata-kata sunnah Allah (sunnatullah) untuk kehidupan manusia dalam sejarahnya. Taqdir digunakan dalam al-Qur’an dalam arti pemastian hukum Allah untuk alam ciptaan-Nya (lihat: QS. Al-Furqon (25):2). Oleh karena itu perjalanan pasti gejala atau benda alam seperti matahari yang beredar pada orbitnya dan rembulan yang nampak berkembang dari bentuk seperti bulan sabit sampai bulan purnama kemudian kembali seperti sabit lagi, semuannya itu disebut sebagai taqdir Allah, karena segi kepastiannya sebagai hukum Allah untuk alam ciptaann-Nya (lihat QS.Yasin (36): 38-39). Doktrin kepastian hukum Allah untuk alam semesta yang disebut taqdir itu juga dinamakan qodar (ukuran yang persis dan pasti). Hal ini misalnya ditegaskan dalam firman Allah : Inna kulla syaik-in khalaqnaahu biqodar (sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan ukuran/ aturan yang pasti, lihat: QS. Al-Qomar (54): 49). Oleh karena itu salah satu makna beriman kepada taqdir atau qodar Tuhan dalam kacamata kosmologis adalah beriman kepada adanya hukum-hukum kepastian yang menguasai alam sebagai ketetapan dan keputusan yang tidak dapat dilawan. Maka manusia tidak bisa tidak harus memperhitungkan dan tunduk kepada hukum-hukum itu dalam amal perbuatannya.2 2 291. Nurcholis Madjid. 1993. Islam Kemodernan dan Ke-Indonesiaan. Bandung: Mizan. Hlm. Landasan Epistemologi... 156 Adanya hukum-hukum Allah bagi seluruh alam semesta, baik mikro maupun makro yang tak terhidarkan itu, yang menguasai kegiatan manusia, menjadi unsur pembatasan dan keterbatasan manusia, tetapi juga disitulah kesempatannya untuk meraih suatu bentuk keberhasilan dalam usaha. Yaitu bahwa manusia akan berhasil atau gagal dalam usahanya setaraf dengan seberapa jauh ia bekerja sesuai taqdir Allah untuk alam lingkungannya yang hukum itu tidak mungkin tertaklukkan. Dan disinilah mulai munculnya pemikiran ilmu pengetahuan. Jadi dapat disimpulkan bahawa Ilmu Pengetahuan itu adalah upaya manusia untuk memahami hukum-hukum Allah yang pasti bagi alam semesta ciptaan-Nya ini. Oleh karena itu ilmu pengetahuan ini mempunyai nilai kebenaran, selama ia secara tepat mewakili (represent) hukum kepastian Allah atau taqdir-Nya itu. Maka ilmu pengetahuan yang benar dengan sendirinya bermanfaat untuk manusia.3 Ilmu pengetahuan diberikan Allah kepada manusia melalui kegiatan manusia sendiri dalam usaha memahami alam raya ini. Hal ini berbeda dengan agama yang diberikan dalam bentuk pengajaran atau pewahyuan lewat para utusan Allah. Perbedaan itu disebabkan oleh perbedaaan objeknya. Apa yang harus dipahami manusia lewat ilmu pengetahuan adalah hal-hal yang lahiriah dengan segala variasinya (seperti hal yang sepintas lalu seperti ghaib atau batiniah misalnya medan magnik atau gravitasi dan kenyataan-kenyataan lain yang menjadi kajian fisika sub atomik dan fisika baru lainnya yang sampai sekarang ini masih dalam perdebatan). Sedangkan yang harus dipahami manusia lewat wahyu adalah kenyataan-kenyataan yang tidak empirik, tidak kasad indera sehingga tidak ada kemungkinan lain mengetahui bagi manusia keculai melalui sikap percaya dan menerima (iman dan Islam) khabar para nabi (wahyu).4 Dalam usaha memahami alam sekitarnya itu manusia harus mengerahkan dan mencurahkan akalnya. Maka alam menjadi objek 3 4 Ibid. Hlm. 292 Ibid. Bab 4 157 pemahaman sekaligus sumber pelajaran hanya bagi mereka yang berakal atau berpikir saja (lihat: QS. Al-Imran (3):190). Oleh karena itu akal bagi manusia bukanlah alat untuk menciptkan kebenaran melainkan untuk memahami atau menemukan kebenaran yang memang semula telah ada dan berfungsi dalam lingkungan di luar diri manusia. Pandangan terhadap alam seperti telah dijelaskan di atas itu barangkali yang telah dianut oleh para ilmuwan muslim pada zaman klasik seperti Al-Biruni, Al-Khawarizmi, Al-Rum, Ibnu Taimiyah, yang sangat terkenal dengan adagium empriknya : Alhaqiqoh fil a’yan la fid-dhon (hakikat itu ada dalam kenyataan luar tidak dalam pikiran). Maka dengan sendirinya akal akan bisa berhasil atau gagal dalam suatu garis kontinum, sesuai dengan tingkat nilai kebenaran pengetahuannya. Misalnya teori Newton lama dianggap benar dan telah pula berfungsi, namun berhadapan dengan perkembangan akal manusia lebih lanjut ternyata tidak dapat dipertahankan sebagian atau seluruhnya. Begitu pula dengan teori-teori Einstein selalu mempunyai potensi untuk terbukti salah. Dalam kaitanya dengan keseluruhan kenyataan kosmis, ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia melalui kegiatan akalnya tidak lain adalah sedikit ilmu yang diberikan Allah. Sedangkan ilmu Allah yakni kebenaran yang serba meliputi (Al-Muhith) adalah tak terbatas. Sehingga di atas setipa orang yang berpengetahuan ada Dia Yang maha Tahu (QS.(12):76) Kenyataan alam ini berbeda dengan prasangka aliran Idelaisme maupun agama Hindu yang mengatakan bahwa alam raya ini tidak mempunyai eksistensi riil dan obyektif, melainkan semu, palsu atau maya dan sekedar emanasi atau panacaran dari dunia lain yang konkrit yaitu ide atau nirwana (lihat:QS. Shod (38):27). Juga bukan seperti yang dikatakan oleh Filasafat Agnoticisme yang beranggapan bahwa alam tidak mungkin dimengerti oleh manusia. Dan sekalipun filsafat Materialisme mengatakan bahwa alam ini mempunyai eksistensi riil dan obyektif, sehingga dapat dimengerti oleh manusia, namun sesatnya adalah meniadakan penciptaan yaitu alam ada dengan sendirinya. 158 Landasan Epistemologi... Di samping terdapat hukum-hukum Tuhan yang pasti yang menguasai alam semesta (taqdir), ada lagi hukum-hukum Tuhan yang tetap dan pasti yang menguasai manusia dalam sejarah kehidupannya. Hukum-hukum Tuhan ini disebut Sunnatullah. Oleh karena itu setelah memahami lingkungan alam hidupnya manusia dituntut untuk memahami lingkungan manusiawinya sendiri yang menjelma dalam sejarah. Sejarah manusia berjalan mengikuti aturan-aturan yang predictable karena kepastiannya sebagimana dibuat oleh Allah sendiri (lihat: QS. Fathir (35): 43) Tetapi, jika ketentuan-ketentuan yang menguasai lingkungan alam itu bersifat netral dari sudut pandangan kepentingan manusia, sebaliknya ketentuan-ketentuan yang menguasai sejarah tidaklah demikian, karena ia menyangkut diri manusia sendiri. Ketentuanketentuan itu sarat dengan nilai-nilai yaitu amat langsung terkait dengan moralitas, yang intinya adalah bahwa kebaikan membawa kesentosaan dan kejahatan membawa kesengsaraan (lihat: QS.Ali Imron (3):137) Demikian manusia dengan intelektualitas yang dimilikinya harus memahami sejarah dengan hukum-hukumnya yang tetap dan pasti. Hukum sejarah yang tetap (sunnatullah) pada garis besarnya adalah bahwa manusia akan menemui kejayaan jika setia kepada kemanusiaan fitrinya dan akan menemui kehancuran jika menyimpang daripadanya dengan menuruti hawa nafsu (lihat : QS. As-Syam (91): 9-10). Cara-cara perbaikan hidup sehingga terus-menerus maju ke arah yang lebih baik sesuai dengan fitrah adalah masalah pengalaman manusia, sehingga pengalaman manusia ini harus ditarik dari masa lampau untuk dapat dimengerti pada masa sekarang kemudian memperhitungkannya ke masa mendatang (lihat:QS.Yusuf 12:111). Melalui memahami sejarah ini manusia harus berjuang membebaskan dirinya dan meningkatkan harkat martabat hidupnya, menguasai dan mengarahkan masyarakat serta membimbingnya ke arah kemajuan dan kebaikan. Ilmu Pengetahuan pada hakikatnya adalah produk upaya manusia untuk memahami hukum-hukum Allah yang tetap dan pasti, baik yang Bab 4 159 menguasai alam semesta maupun diri manusia dalam sejarah (taqdir dan sunnah-Nya) yang diberlakukan Allah untuk seluruh ciptaan-Nya. Oleh karena itu Ilmu Pengetahuan mempunyai nilai kebenaran (walau kadarnya relatif) selama secara tepat dapat mewakili hukum ketetapan dan kepastian Allah itu (taqdir dan sunnah-Nya). Maka ilmu pengetahuan yang benar dengan sendirinya akan bermanfaat bagi manusia. Pemahaman manusia dengan akal pikirannya terhadap alam semesta ini yang di dalamnya terdapat hukum-hukum Tuhan yang pasti dan tetap (taqdir) dalam perkembangannya telah melahirkan Ilmu-ilmu Kealaman dengan segala percabangannya. Sedangkan pemahaman manusia dengan akal pikiranya yang sempurna itu terhadap sejarah dan kemanusiaannya yang mana di dalamnya juga terdapat hukumhukum Tuhan yang tetap dan pasti (sunnah) itu dalam perkembangannya telah melahirkan Ilmu-ilmu Sosial dan Kemanusiaan (Humaniora) dengan segala percabangannya. Kegiatan inilah pada hakekatnya saat lahirnya Ilmu Pengetahuan dan peradaban umat manusia di dunia. Oleh karena hukum-hukum Allah (sunnah dan taqdir-Nya) itu merupakan gejala nyata sekeliling hidup manusia, maka dapat dikatakan bahwa semua peradaban manusia berupaya memahaminya (tanpa kecuali, baik yang beriman maupun yang tidak, Islam atau tidak) secara umum untuk seluruh ummat manusia di dunia. Dari hasil pemahamannya itu melahirkan Filsafat (segi spekulatifnya) dan Ilmu Pengetahuan (segi empiriknya). Oleh karena itu untuk memahami hukumhukum Allah itu kita dianjurkan dan diberi petunjuk oleh Nabi Muhammad SAW agar kita belajar dari siapa saja, sekalipun sampai ke negeri Cina. Nabi juga menegaskan bahwa hikmah (yakni setiap kebenaran dalam falsafah, ilmu pengetahuan, dll) adalah barang hilangnya kaum beriman, oleh karena itu siapa saja yang menemukannya hendaknya ia memungutnya dan hendaknya kita memungut hikmah kebenaran dan tidak akan berpengaruh buruk kepada kita dari bejana apapun hikmah kebenaran itu keluar. Bahkan menurut riwayat, Nabi Landasan Epistemologi... 160 sendiri memberi contoh mengirim para sahabat ke Jundaishapur Persia guna belajar ilmu kedokteran dari kaum Hellenis di sana.5 Dari uraian ini kiranya dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa Ilmu Pengetahuan itu baik yang alamiah maupun yang sosial dari segi produk pemahaman manusia sifatnya netral. Artinya ilmu sebagai produk pemahaman manusia akan fenomena alam, sejarah dan kemanusiaan, dilihat dari kacamata moral etik tidak mengandung nilai kebaikan dan kejahatan pada dirinya. Nilainya diberikan oleh manusia yang memiliki dan menguasainya. Sebagaimana dengan apa saja yang netral, ilmu pengetahuan dapat diterapkan dan dipergunakan baik untuk tujuan-tujuan baik maupun untuk tujuan-tujuan yang buruk (merusak). Netralitas Ilmu pengetahuan inilah yang memungkinkan untuk dapat ditukar-menukarkan atau diberi dan dimintakan antara sesama manusia tanpa memandang tata nilai masing-masing yang bersangkutan. Nilai yang ada pada sebuah ilmu adalah nilai kebenaran itu sendiri, walaupun kadarnya relatif. Ilmu Pengetahuan dalam dirinya tidak berbicara baik dan buruk tetapi berbicara tentang benar dan salah sesuai akurasi dan validitas metodologi yang diperguanakan. Oleh karena netralitas ilmu pengetahuan itu lepas dari membicarakan baik dan buruk, maka dalam tataran praktisnya yaitu penerapan konsep-konsep ilmiah yang menjelma menjadi bentuk Teknologi itu harus ditundukkan dibawah pertimbangan-pertimbangan fitrah kemanusiaan. Ia tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri tanpa bimbingan kesadaran kemanusiaan sehingga dapat memberi umpan balik yang merusak kehidupan. Jangan sampai terjadi kerusakan di darat maupun di laut akibat perbuatan tangan-tangan kotor manusia (lihat: QS.(30):41). Penerapan Ilmu Pengetahuan mengharuskan bimbingan akhlaq Tuhan (moralitas robbaniyah) yang harus mematuhi rasa cinta kasih yang kita tiru dari akhlaq Allah, terutama sifat kasih dan sayang-Nya ( rahman dan rahim-Nya). Ilmu Pengetahuan sebagai cara untuk mengenali 5 Ibid. Bab 4 161 lingkungan secara lebih baik guna lebih membantu kehidupan manusia hendaknya hanya ditujukan kepada penggunaan bagi peningkatan kehidupan yang diliputi oleh semangat rasa cinta kasih. Maka sangat simbolis sekali dalam ajaran Islam setiap mengawali aktifitas dengan ucapan “basmalah” yang mana disebutkan dua kali sifat Tuhan yang serba kasih dan sayang. Ini menyangkut nilai intelektualitas di kalangan kaum muslimin. Bukan persoalan mutu (kualitas) suatu pekerjaan. Mengenai soal mutu pekerjaan umat Islam juustru harus belajar banyak, termasuk dari kalangan non-muslim, sebagaimana dulu pernah dilakukan pada zaman kejayaan Islam klasik dan sekarang ini walupun sangat lamban sedang berjalan. D. Paradigma Profetik dalam Hukum Islam Melalui Pendekatan Systems * Oleh Amin Abdullah 1. Pendahuluan Paradigma profetik atau paradigm hukum Islam yang pro(f)etik diminati kembali oleh beberapa kalangan akademisi dan inteligensia untuk membantu masyarakat Muslim kontemporer keluar dari kesulitan-kesulitan yang dihadapinya sekarang ini, baik pada dataran lokal maupun global-internasional. Tulisan ini menegaskan bahwa paradigma profetik tidak dapat terlepas dari perjalanan sejarah pemikiran Islam dalam perjumpaannya dengan sejarah panjang perkembangan pemikiran umat manusia pada umumnya dan sekaligus dalam pergumulannya dengan konstruksi bangunan filsafat keilmuan Islamic Studies/Dirasat Islamiyyah dari setiap era yang dilaluinya (Tradisional, Modern dan Postmodern). Kedua dimensi ini, yaitu waktu Makalah disampaikan dalam “Serial Diskusi Menggagas Ilmu Hukum Berparadigma Profetik sebagai Landasan Pengembangan Pendidikan Hukum di Fakultas Hukum UII – Seri III, Yogyakarta, 12 April 2012. * 162 Landasan Epistemologi... (history) dan pemikiran (thought) tidak dapat terpisah, tetapi menyatu. Oleh karenanya, paradigma profetik hukum Islam kontemporer tidak dapat melepaskan diri dari pergumulannya dengan sains modern, ilmuilmu sosial dan humaniora kontemporer. Pendekatan Systems yang hendak diperkenalkan dalam tulisan ini diharapkan akan dapat membantu upaya untuk menyusun kembali paradigma baru hukum Islam yang peka dan bermuatan nilai-nilai profetik kontemporer, khususnya oleh masyarakat Muslim kontemporer dalam perjumpaan mereka dengan komunitas dan budaya lokal di masing-masing negara (local citizenship) dan sekaligus dalam perjumpaannya dengan komunitas dan budaya global-internasional (world citizenship). Tanpa mempertimbangkan kedua sisi tersebut, bangunan paradigma pro(f)etik yang dicita-citakan akan kehilangan signifikansi dan elan vitalnya. 2. Respon Intelektual Muslim terhadap Perubahan Sosial Kontemporer Tidak ada yang dapat menyangkal jika dikatakan bahwa dalam 150 sampai 200 tahun terakhir, sejarah umat manusia mengalami perubahan yang luar biasa. Terjadi perubahan yang luar biasa dalam sejarah manusia dalam mengatur dan memperbaiki kualitas kehidupannya. Perubahan yang dahsyat dalam perkembangan ilmu pengetahuan, tatanan sosial-politik dan sosial-ekonomi, hukum, tata kota, lingkungan hidup dan begitu seterusnya. Perubahan dahsyat tersebut, menurut Abdullah Saeed, antara lain terkait dengan globalisasi, migrasi penduduk, kemajuan sains dan teknologi, eksplorasi ruang angkasa, penemuan-penemuan arkeologis, evolusi dan genetika, pendidikan umum dan tingkat literasi. Di atas itu semua adalah bertambahnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya harkat dan martabat manusia (human dignity), perjumpaan yang lebih dekat antar umat beragama (greater inter-faith interaction), munculnya konsep negara-bangsa yang berdampak pada kesetaraan dan perlakuan yang sama kepada semua warga negara (equal citizenship), belum lagi Bab 4 163 kesetaraan gender dan begitu seterusnya. Perubahan sosial yang begitu dahsyat tersebut berdampak luar biasa dan mengubah pola berpikir dan pandangan keagamaan (religious worldview) baik di lingkungan umat Islam maupun umat beragama yang lain.6 Dalam khazanah pemikiran keagamaan Islam, khususnya dalam pendekatan Usul al Fikh, dikenal istilah al-Tsawabit (hal-hal yang diyakini atau dianggap tetap, tidak berubah) wa al-Mutaghayyirat (hal-hal yang diyakini atau dianggap berubah-ubah, tidak tetap). Ada juga yang menyebutnya sebagai al-Tsabit wa al-Mutahawwil. 7 Sedang dalam pendekatan Falsafah (philosophy), sejak Aristotle hingga sekarang, juga dikenal apa yang disebut Form and Matter.8 Belakangan di lingkungan khazanah keilmuan antropologi (agama), khususnya dalam lingkup kajian penomenologi agama, dikembangkan analisis pola pikir keagamaan yang biasa disebut General Pattern dan Particular Pattern.9 Adalah merupakan pertanyaan yang sulit dijawab bagaimana kedua Abdullah Saeed. 2006. Interpreting the Qur’an: Towards a contemporary approach, New York: NY, Routledge. Hlm. 2 7 Adonis. 2002. al-Tsabit wa al-Mutahawwil: Bahts fi al-ibda’ wa al-itba’ ‘inda al-arab. London: Dar al-Saqi. 8 Menurut penelitian Josep van Ess, disini lah letak perbedaan yang mencolok antara logika dan cara berpikir Mutakallimun dan Fuqaha di satu sisi dan Falasifah di sisi lain. “Aristotelian definition, however, presupposes an ontology of matter and form. Definition as used by the mutakallimun usually does not intend to lift individual phenomena to a higher, generic category; it simply distinguishes them from other things (tamyiz). One was not primarily concerned with the problem how to find out the essence of a thing, but rather how to circumscribe it in the shortest way so that everybody could easily grasp what was mean”. Lebih lanjut Josep van Ess, “The Logical Structure of Islamic Theology”, dalam Issa J. Boullata (Ed.), An Anthology of Islamic Studies, Canada, McGill Indonesia IAIN Development Project, l992, tanpa halaman. Cetak miring dan hitam dari saya. Jasser Auda menambahkan bahwa “ … the jurists’ method of tamyiz between conceps, whether essence-or description-based always resulted in defining every concept in relation to a ‘binary opposite.’ The popular Arabic saying goes: “Things are distinguished based on their opposites’ (bizdiddiha tatamayyaz al-ashya’)”. Lihat Jasser Auda. 2008. Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Sistems Approach. London dan Washington: The International Institute of Islamic Thought. Hlm. 212. 9 Richard C. Martin menyebut ‘general pattern’ sebagai ‘common pattern’ atau the universals of human religiousness. Lebih lanjut Richard C. Martin, (Ed.) 1985. Approaches to Islam in Religious Studies, Arizona, The University of Arizona Press. Hlm. 8. 6 164 Landasan Epistemologi... atau ketiga alat ‘logika berpikir’ tersebut dapat dioperasionalisasikan di lapangan ketika umat Islam menghadapi perubahan sosial yang begitu dahsyat. Dalam praktiknya, tidak mudah mengoperasionalisasikannya di lapangan pendidikan, sosial, dakwah, hukum dan begitu seterusnya, karena masing-masing orang dan kelompok telah terkurung dalam preunderstanding yang telah dimiliki, membudaya dan dalam batas-batas tertentu bahkan membelenggu. Oleh karenanya, banyak keraguan dan benturan di sana sini, baik pada tingkat person-person atau individu-individu, lebih-lebih pada tingkat sosial dan kelompok-kelompok. Seringkali kedua atau ketiga alat analisis entitas berpikir dalam dua tradisi khazanah keilmuan yang berbeda ini, yakni Usul al-Fikh (wilayah agama) dan Falsafah (philosophy) (wilayah sains) bertentangan, berbenturan dan berseberangan. Masih jauh dari upaya ke arah perkembangan menuju ke dialog dan integrasi.10 Perbedaan yang tajam antara kedua tradisi keilmuan dan corak berpikir dalam menganalisis dan memetakan persoalan sosial-keagamaan yang dihadapi dan jalan keluar yang hendak diambil inilah yang menjadi topik sentral dalam rancang bangun epistemologi keilmuan Islam kontemporer, yang sedang dicoba dirumuskan ulang secara serius oleh para pembaharu pemikiran Islam antara lain seperti Muhammad Abduh, Mohammad Iqbal, Fazlur Rahman dan pemikir Muslim kontemporer seperti yang sebagian pemikirannya akan saya bicarakan di sini, Abdullah Saeed dan Jasser Diskusi dan pembahasan serius tentang hubungan antara agama dan ilmu (Religion and Science) di tanah air, kalau saya tidak salah mengamati, sangat jarang dilakukan. Kalaupun dilakukan masih dilakukan secara sporadis, tidak terprogram dan terencana. Jika Ian Barbour memetakan ada 4 pola hubungan antara keduanya, yaitu Konflik, Independen, Dialog dan Integrasi, maka yang banyak dijumpai sekarang, bahkan di perguruan tinggi sekalipun, adalah masih dalam tahapan Konflik atau paling maju adalah Independen. Belum sampai pada taraf Dialog apalagi Integrasi. Lebih lanjut Ian G Barbour. 1966. Issues in Religion and Science, New York, Harper Torchbooks. Juga Holmes Rolston, III, Science and Religion: A Critical Survey, New York: Random House. Dalam pemikiran Islam yang sampai ke tanah air masih sangat jarang dilakukan. Upaya-upaya awal dilakukan oleh Mohammad Abid al-Jabiry. 2002. Madkhal ila Falsafah al-Ulum: alAqlaniyyah al-Mu’asirah wa Tathawwur al-Fikr al-Ilmy, Beirut: Markaz Dirasaat al-Wihadah al-Arabiyyah, Cetakan ke 5. juga Mohammad Shahrur. 2000. Nahw Usul al-Jadidah li alFiqh al-Islamy: Fiqh al-Mar’ah, Damaskus: al-Ahali. 10 Bab 4 165 Auda. Pemikiran muslim kontemporer masih banyak yang lain, seperti Kuntowijoyo dan lain-lain. Mengangkat tema Epistemologi Islam (komunitas lokal) dan Globalisasi (komunitas internasional) dalam satu keutuhan pembahasan berarti harus ada kesediaan untuk mempertemukan dan mendialogkan antara kedua model entitas berpikir yang sulit di atas. Tidak bisa membicarakan yang satu dan meninggalkan yang lain. Kecuali, kalau topik pembahasan diubah menjadi hanya membicarakan salah satu diantara kedua tema tersebut. Membicarakan Epistemologi Islam saja atau hanya globalisasi saja. Di sini sulitnya mengangkat tema pembahasan seperti di atas, karena para pelaku di lapangan harus bersedia mendialogkan, mendekatkan dan mempertemukan antara keduanya secara adil, proporsional dan bijak. Harus ada kesediaan dan mentalitas untuk saling ‘take’ and ‘give’, saling mendekat, dialog, konsensus, kompromi dan negosiasi. Tidak boleh ada pemaksaan kehendak. Tidak ada pula perasaan merasa ditinggal. Oleh karenanya, perlu disentuh bagaimana struktur bangunan dasar yang melandasi cara berpikir umat manusia secara umum dan sekaligus juga harus disentuh bagaimana bangunan dasar cara berpikir keagamaan Islam secara khusus. Ketika menyebut Epistemologi Islam, mau tidak mau harus bersentuhan dengan keilmuan atau pendekatan Usul al-Fiqh, sedang menyebut Globalisasi – yang melibatkan pengalaman umat manusia pada umumnya - mau tidak mau perlu mengenal cara berpikir secara lebih umum ruang lingkupnya, sehingga harus bersentuhan dan berkenalan dengan metode Filsafat dan metode berpikir sains pada umumnya. Dalam bingkai payung besar perspektif seperti itu, dalam tulisan ini, saya akan membawa peta percaturan dunia epistemologi Islam dalam menghadapi dunia global lewat tiga pemikir Muslim kontemporer, yaitu Abdullah Saeed dari Australia dan Jasser Auda dari London.11 Ada Sudah barang tentu masih banyak sekali pemikir Muslim kontemporer yang lain yang mempunyai concern dan keprihatinan yang sama, seperti Mohammad Shahrur (Syiria),Abdul Karim Soroush (Iran), Fatimah Mernissi, Riffat Hassan, Hasan Hanafi (Mesir), Nasr Hamid Abu Zaid (Mesir), Farid Esack (Afrika Selatan), Ebrahim Moosa (Afrika 11 166 Landasan Epistemologi... beberapa alasan mengapa dipilih dua pemikir Muslim kontemporer tersebut. Pertama, adalah karena mereka hidup di tengah-tengah era kontemporer, di tengah-tengah arus deras era global sekarang ini. Kedua, mereka datang dari belahan duni yang berbeda, yaitu Australia dan Eropa, namun keduanya mempunyai basis pendidikan Islam Tradisional dari negara yang berpenduduk Muslim (Maldev dan Mesir). Ketiga, keduanya sengaja dipilih untuk mewakili suara ‘intelektual’ minoritas Muslim yang hidup di dunia Barat, di wilayah mayoritas non-Muslim. Dunia baru tempat mereka tinggal dan hidup sehari-hari bekerja, berpikir, melakukan penelitian, berkontemplasi, berkomunitas, bergaul, berinteraksi, berperilaku, bertindak, mengambil keputusan. Mereka hidup di tempat yang sama sekali berbeda dari tempat mayoritas Muslim dimanapun mereka berada. Keduanya mengalami sendiri bagaimana mereka harus berpikir, mencari penghidupan, berijtihad, berinteraksi dengan negara dan warga setempat, bertindak dan berperilaku dalam dunia global, tanpa harus menunggu petunjuk dan fatwa-fatwa keagamaan dari dunia mayoritas Muslim. Keempat, kedua pemikir, penulis, dan peneliti tersebut - dalam kadar yang berbeda-beda - mempunyai kemampuan untuk mendialogkan dan mempertautkan antara paradigma Ulumu al-Din, alFikr al-Islamiy dan Dirasat Islamiyyah kontemporer dengan baik. Yakni, Ulumu al Din atau biasa disebut al-Turats (Kalam, Fiqh, Tafsir,Ulum alQur’an, Hadis) yang telah didialogkan, dipertemukan dengan sungguhsungguh - untuk tidak menyebutnya diintegrasikan - dengan Dirasat Islamiyyah atau al-Hadatsah yang menggunakan sains modern, social sciences dan humanities kontemporer sebagai pisau analisisnya dan cara berpikir keagamaannya.12 Selatan), Abdullahi Ahmed al-Naim (Sudan), Tariq Ramadan, Omit Safi, Khaled Aboe el-Fadl dan lain-lain seperti Mohammad Arkoun, Muhammad Abid al-Jabiry (Marokko), belum lagi para pemikir muslim dari tanah air. Pengalaman saya mengajar di program paska sarjana IAIN dan UIN, dan lebih-lebih program S1, masih jarang mahasiswa yang mengetahui dengan baik metode dan buah pikiran para pemikir Muslim yang menggunakan paradigma Dirasat Islamiyyah kontemporer ini. 12 Saya telah mengelaborasi hubungan antara ketiga kluster keilmuan Islam, yaitu antara Ulum al-Din, al-Fikr al-Islamy dan Diirasat Islamiyyah dalam tulisan saya “Mempertautkan Bab 4 167 Dengan kata lain, globalisasi yang dinyatakan dalam judul tulisan ini adalah Globalisasi dalam praktik, globalisasi dalam praktik hidup sehari-hari, dan bukannya globalisasi dalam teori yang belum masuk dalam wilayah praktik. Yaitu dunia global seperti yang benar-benar dialami dan dirasakan sendiri oleh para pelakunya di lapangan, yang sehari-hari memang tinggal dan hidup di negara-negara sumber dari globalisasi dan modernitas itu sendiri, baik dari segi transportasi, komunikasi, ekonomi, sains, teknologi, budaya dan begitu seterusnya. Bukan globalisasi yang diteoritisasikan dan dibayangkan oleh para intelektual Muslim yang tinggal dan hidup di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, dan tidak atau belum pernah merasakan bagaimana tinggal dan hidup sehari-hari di negara-negara non-Muslim, pencetus dan penggerak roda globalisasi. Lewat lensa pandang seperti itu, ada hal lain yang hendak ditegaskan pula disini bahwa manusia Muslim yang hidup saat sekarang ini dimanapun mereka berada adalah warga dunia (global citizenship), untuk tidak mengatakan hanya terbatas sebagai warga lokal (local citizenship). Sudah barang tentu, dalam perjumpaaan antara local dan global citizenship ini ada pergumulan epistemologis dan pergulatan identitas yang tidak mudah. Ada dinamika dan dialektika antara keduanya, antara being a true Muslim dan being a member of global citizenship sekaligus, yang berujung pada pencarian sintesis baru yang dapat memayungi dan menjadi jangkar spiritual bagi mereka yang hidup dalam dunia baru dan dalam arus pusaran perjumpaan dengan orang atau kelompok lain dan perubahan sosial yang global sifatnya. Selain itu, juga ingin menyadarkan manusia Muslim yang tinggal di negara-negara Muslim mayoritas, bahwa di sana ada genre baru kelompok masyarakat dan corak intelektual Muslim yang tumbuh berkembang di wilayah benua-benua non-Muslim. Bicara umat Islam sekarang, tidak lagi cukup, bahkan tidak lagi valid hanya menyebut secara konvensional seperti Kairo, Teheran, Karachi, Jakarta, Ulum al-Din, Al-Fikr al-Islamy dan Dirasat al-Isalimyyah: Sumbangan Keilmuan Islam untuk Peradaban Global” dalam Marwan Saridjo (Ed), Mereka Bicara Pendidikan Islam: Sebuah Bunga Rampai, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009, h.261-298. 168 Landasan Epistemologi... Kualalumpur, Istanbul atau Riyadh tetapi sekarang kita juga perlu belajar menerima kehadiran Muslim dari London, Koln, Berlin, Paris, Melbourne, Washington DC, Michigan, Huston, New York, Chicago dan lain-lain. 3. Progressif-ijtihadi dalam Tafsir al-Qur’an: Abdullah Saeed Jabatan yang dipegang saat ini adalah Direktur pada Asia Institute, Universitas Melbourn e, Direktur Center for the Study of Contemporary Islam, University of Melbourne, Sultan Oman Professor of Arab and Islamic Studies, University of Melbourne, Adjunct Professor pada Faculty of Law, University of Melbourne. Riwayat pendidikan: Arabic Language Study, Institute of Arabic Language, Saudi Arabia, l977-79, High School Certificate, Se condary Institute, Saudi Arabia, l979-82; Bachelor of Arts, Arabic Literature and Islamic Studies, Islamic University, Saudi Arabia, l982-l986; Master of Arts Preliminary, Middle Eastern Studies, University of Melbourne, Australia, Master of Arts, Applied Linguistics, University of Melbourne, Australia, l992-l994; Doctor of Philosophy, Islamic Studies, University of Melbourne, Australia, l988-l992. Karya tulis baik yang berupa buku, makalah ataupun tulisan lepas banyak sekali dalam berbagai bidang yang bervariasi. Kecenderungan tema yang ditulis adalah tentang Islam dan Barat, al-Qur’an dan Tafsir, serta tentang Tren Kontemporer Dunia Islam termasuk ekonomi Islam dan Jihad/ Terrorisme. Diantaranya Interpreting the Qur’an: Towards a Contemporary Approach (London: Routledge, 2006); “Muslim in the West and their Attitude to Full Participating in Western Societies: Some Reflections” dalam Geoffrey Levey (ed.), Religion and Multicultural Citizenship (Cambridge: Cambridge University Press, 2006); “Muslim in the West Choose Between Isolationism and Participation” dalam Sang Seng, Vol 16, Seol: Asia-Pacific Center for education and International Understanding/UNESCO, 2006); “Jihad and Violence: Changing Understanding of Jihad among Muslims” dalam Tony Coady and Michael O’Keefe (eds.), Terrorism and Violence (Melbourne: Melbourne University Press, 2002); dan risetnya yang Bab 4 169 berjudul ‘Reconfiguration of Islam among Muslims in Australia (20042006)’. Abdullah Saeed adalah cendekiawan Muslim yang berlatar belakang pendidikan bahasa dan sastra Arab serta studi Timur Tengah. Kombinasi institusi pendidikan yang diikuti, yaitu pendidikan di Saudi Arabia dan karir akademik di Melbourne Australia menjadikannya kompeten untuk menilai dunia Barat dan Timur secara objektif. Saeed sangat konsern dengan dunia Islam kontemporer. Pada dirinya ada spirit bagaimana ajaran-ajaran Islam itu bisa shalih li kulli zaman wa makan, dalam paham minoritas Muslim yang tinggal di negara Barat. Spirit semacam inilah yang ia sebut sebagai Islam Progressif. Subjeknya disebut Muslim Progressif. Islam progressif adalah merupakan upaya untuk mengaktifkan kembali dimensi progressifitas Islam yang dalam kurun waktu yang cukup lama mati suri ditindas oleh dominasi teks. Dominasi teks ini oleh Mohammad Abid al-Jabiry disebut sebagai dominasi epistemologi atau nalar Bayani dalam pemikiran Islam. Metode berpikir yang digunakan oleh Muslim Progressif inilah yang disebutnya dengan istilah progressif - ijtihadi. Sebelum dipaparkan bagaimana kerangka kerja progressif-Ijtihadi ini, ada baiknya dilihat posisi Muslim progressif dalam trend pemikiran Islam yang ada saat ini. Menurut Saeed, ada enam kelompok pemikir Muslim era sekarang, yang corak pemikiran keagamaan berikut epistemologi hukumnya berbeda-beda (l) The Legalist-traditionalist, yang titik tekannya ada pada hukum-hukum yang ditafsirkan dan dikembangkan oleh para ulama periode pra Modern; (2) The Theological Puritans, yang fokus pemikirannya adalah pada dimensi etika dan doktrin Islam; (3) The Political Islamist, yang kecenderungan pemikirannya adalah pada aspek politik Islam dengan tujuan akhir mendirikan negara Islam; (4) The Islamist Extremists, yang memiliki kecenderungan menggunakan kekerasan untuk melawan setiap individu dan kelompok yang dianggapnya sebagai lawan, baik Muslim ataupun non-Muslim; (5) The Secular Muslims, yang beranggapan bahwa agama merupakan urusan pribadi (private matter); dan (6) The 170 Landasan Epistemologi... Progressive Ijtihadists, yaitu para pemikir modern atas agama yang berupaya menafsir ulang ajaran agama agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat modern. Pada kategori yang terakhir inilah posisi Muslim progressif berada.13 Karakteristik pemikiran Muslim progressif-ijtihadis, dijelaskan oleh Saeed dalam bukunya Islamic Thought adalah sebagai berikut: (1) mereka mengadopsi pandangan bahwa beberapa bidang hukum Islam tradisional memerlukan perubahan dan reformasi substansial dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Muslim saat ini; (2) mereka cenderung mendukung perlunya fresh ijtihad dan metodologi baru dalam ijtihad untuk menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer; (3) beberapa diantara mereka juga mengkombinasikan kesarjanaan Islam tradisional dengan pemikiran dan pendidikan Barat modern; (4) mereka secara teguh berkeyakinan bahwa perubahan sosial, baik pada ranah intelektual, moral, hukum, ekonomi atau teknologi, harus direfleksikan dalam hukum Islam; (5) mereka tidak mengikutkan dirinya pada dogmatism atau madzhab hukum dan teologi tertentu dalam pendekatan kajiannya; dan (6) mereka meletakkan titik tekan pemikirannya pada keadilan sosial, keadilan gender, HAM, dan relasi yang harmonis antara Muslim dan non-Muslim. Sekilas tampak jelas bahwa corak epistemologi keilmuan Islam kontemporer, dalam pandangan Saeed, adalah berbeda dari corak epistemologi keilmuan Islam tradisional. Penggunaan metode kesarjanaan Abdullah Saeed. 2003. Islamic Thought: An Introduction, London and New York: Routledge. Hlm. 142-50. Untuk lebih detil, dapat juga dibaca Omit Safi (Ed.). 2003. Progressive Muslims: On Justice, Gender and Pluralism, Oxford: Oneworld Publications. Tariq Ramadan juga menengarai ada 6 kecenderungan pemikiran Islam abad akhir abad ke 20 dan abad ke 21, yaitu Scholastic Traditionalism, Salafi Literalism, Salafi Reformism, Political Literalist Salafism, Liberal or Rational Reformism, dan Sufism. Lebih lanjut Tariq Ramadan.2004. Western Muslims and the Future of Islam, New York: Oxford University Press. Hlm. 24-28. Kategorisasi dan klasifikasi trend pemikiran Islam oleh Saeed dan Tariq Ramadan ini memang berbeda dari yang biasa dikenal di tanah air tahun 80an, ketika para ilmuan lebih menekankan pada perbedaan antara Traditionalism dan Modernism, yang kemudian muncul dalam nama mata kuliah seperti Aliran Modern dalam Islam (Modern Trend in Islam). 13 Bab 4 171 dan epistemologi tradisional masih ada, dimana nash-nash al-Qur’an menjadi titik sentral berangkatnya, tetapi metode penafsirannya telah didialogkan, dikawinkan dan diintegrasikan dengan penggunaan epistemologi baru, yang melibatkan social sciences dan humanities kontemporer dan filsafat kritis (Critical Philosophy). Abdullah Saeed memang tidak menyebut penggunaaan metode dan pendekatan tersebut secara eksplisit di situ, tetapi pencantuman dan penggunaaan istilah ‘pendidikan Barat modern’ adalah salah satu indikasi pintu masuk yang dapat mengantarkan para pecinta studi Islam kontemporer ke arah yang saya maksud. Juga isu-isu dan persoalan-persoalan Humanities kontemporer terlihat nyata ketika Saeed menyebut Keadilan sosial, lebih-lebih keadilan Gender, HAM dan hubungan yang harmonis antara Muslim dan nonMuslim. Persoalan humanities kontemporer tidak akan dapat dipahami, dikunyah dan disimpulkan dengan baik, jika epistemologi keilmuan Islam masih menggunakan metode dan pendekatan Ulum al-Din lama. Dalam Epilogue, Bab 12, Abdullah Saeed menjelaskan pandangan dan kritiknya terhadap Ilmu-ilmu Syari’ah (lama), yang terdiri dari hadist, usul al-fiqh dan tafsir jika hanya berhenti dan puas dengan menggunakan metode, cara kerja dan paradigma yang lama. Kemudian, dalam hal tafsir, dia mengajukan metode alternatif untuk dapat memahami teks-teks kitab suci sesuai dengan perkembangan dan tuntutan tingkat pendidikan umat manusia era sekarang ini. Tampak jelas bahwa Abdullah Saeed meneruskan dan mengembangkan lebih lanjut metode tafsir al-Qur’an, yang lebih bernuansa hermeneutis, dari pendahulunya Fazlur Rahman.14 Abdullah Saeed, ibid. Hlm. 145-154. Bandingkan dengan pandangan Ibrahim AbuRabi’ yang mengkritik model pendidikan Islam Tradisional dan Literalist era sekarang yang masih mem-bid’ah-kan kajian ilmu-ilmu sosial (sociology; anthropology) dan filsafat kritis (Critical Philosophy) dalam pendidikan Islam pada level apapun. “The core of the field revolves around Shari’ah and Fiqh studies that have, very often, emptied of any critical or political content, or relevance to the present situation… Furthermore, the perspective of the social sciences or critical philosophy is regrettably absent…The discipline of the sociology of religion is looked upon as bid’ah, or innovation, that does not convey the real essence of Islam.”. Lebih lanjut Ibrahim M. Abu-Rabi’, “A Post-September 11 Critical Assessment of Modern Islamic History”, dalam Ian 14 172 Landasan Epistemologi... Meskipun dirasakan begitu penting dan mendesaknya kebutuhan untuk melakukan perubahan paradigma (shifting paradigm) dalam rumusan dan konstruksi pemikiran Islam kontemporer, khususnya dalam bidang tafsir al-Qur’an, namun tetap saja masih dirasakan betapa sulitnya untuk diterapkan dalam alam pikiran Islam kontemporer. Upaya Abdullah Saeed ini kemudian diteruskan oleh Jasser Auda yang juga mencoba mengenalkan dan menggunakan pendekatan Systems dalam pemikiran hukum Islam khususnya dan studi hukum pada umumnya. 4. Pendekatan Systems Jasser Auda dalam Hukum Islam: Adalah Associate Professor di Fakultas Studi Islam Qatar (QFTS) dengan fokus kajian Kebijakan Publik dalam program Studi Islam. Dia adalah anggota pendiri Persatuan Ulama Muslim Internasional, yang berbasis di Dublin; anggota Dewan Akademik Institut Internasional Pemikiran Islam di London, Inggris; anggota Institut Internasional Advanced Sistem Research (IIAS), Kanada; anggota pengawas Global Pusat Studi Peradaban (GCSC), Inggris; anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuan Muslim Sosial (AMSS), Inggris; anggota Forum perlawanan Islamofobia dan Racism (FAIR), Inggris dan konsultan untuk Islamonline.net. Ia memperoleh gelar Ph. D dari university of Wales, Inggris, pada konsentrasi Filsafat Hukum Islam tahun 2008. Gelar Ph. D yang kedua diperoleh dari Universitas Waterloo, Kanada, dalam kajian Analisis Sistem tahun 2006. Master Fiqh diperoleh dari Unversitas Islam Amerika, Michigan, pada fokus kajian Tujuan Hukum Islam (Maqasid al-Syari’ah) tahun 2004. Gelar BA diperoleh dari jurusan Islamic Studies pada Islamic American University, USA, tahun 2001 dan gelar BSc diperoleh dari Engineering Cairo University, Egypt Course Av., tahun l988. Ia memperoleh pendidikan al-Qur’an dan ilmu-ilmu Islam di Masjid al-Azhar, Kairo. Markham and Ibrahim M. Abu-Rabi’ (Eds.) 11 September: Religious Perspectives on the Causes and Consequences ,Oxford, Oneworld Publications, 2002, h.34 dan 36.Cetak hitam dari saya. Bab 4 173 Jasser Auda adalah direktur sekaligus pendiri Maqasid Research Center di Filsafat Hukum Islam di London, Inggris, dan menjadi dosen tamu untuk fakultas Hukum Universitas Alexandria, Mesir, Islamic Institute of Toronto, Kanada dan Akademi Fiqh Islam, India. Dia menjadi dosen mata kuliah hukum Islam, Filsafat, dan materi yang terkait dengan isu-isu minoritas Muslim dan Kebijakan di beberapa negara di seluruh dunia. Dia adalah seorang contributor untuk laporan kebijakan yang berkaitan dengan minoritas Muslim dan pendidikan Islam kepada Kementrian Msyarakat dan Dewan Pendanaan Pendidikann Tinggi Inggris, dan telah menulis sejumlah buku, yang terakhir dalam bahasa Inggris, berjudul Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law : A Sistems Approach, London, IIIT, 2008. Tulisan yang telah diterbitkan 8 buku dan ratusan tulisan dalam bentuk jurnal, tulisan media, kontribusi tulisan di buku, DVD, ceramah umum, dan jurnal online yang tersebar di seluruh dunia. Selain itu, banyak penghargaan yang telah ia terima.15 Dari otobiograpi di atas tergambar bagaimana seorang Jasser Auda bergumul dalam ijtihad dan jihad berpikir untuk memperbaharui epistemology dan mereformasi hukum Islam tradisional. Baginya, setiap klaim yang menyatakan bahwasanya pintu ijtihad tidak tertutup atau membuka pintu ijtihad adalah merupakan suatu keharusan mengalami jalan buntu (Intellectual impasse) karena menurutnya belum tergambar secara jelas bagaimana metode dan pendekatan yang digunakan dan bagaimana aplikasi dan realisasinya di lapangan. Seperti Mohammad Shahrur dari Syiria, dia adalah berlatar belakang pendidikan teknik/ insinyur. Berbekal keahlian dalam dua bidang keilmuan, yaitu metode sains dan metode agama inilah ia ingin menyumbangkan keahlian dan keilmuannya untuk membantu rekan-rekannya yang menghadapi jalan buntu intelektual ketika hendak membuka pintu ijtihad. Kebuntuan intelektual ini pada gilirannya akan berdampak pada sikap etis atau non-etisnya umat beragama. Lebih jauh tentang Jasser Auda dapat dilacak www.jasserauda.net dan juga www.maqasid.net 15 174 Landasan Epistemologi... Karir studi akademiknya pun ia rancang sedemikian terprogram sejak dari mulai menguasai bidang Fiqh, Usul al-Fiqh, Hukum Islam, teori Maqasid sampai menguasai teori Sistems dengan baik pada tingkat doktor (ijazah doktor pertama yang diperolehnya dari Kanada hanya untuk memantapkan keahliannya menguasai teori Sistem dalam pengetahuan manusia). Sekumpulan pengetahuan dengan berbagai pendekatan inilah yang ia himpun untuk menunjang karir akademiknya yang telah lama ia idam-idamkan untuk membantu membuka kembali pintu ijtihad yang telah lama terbuka tapi tidak ada yang berani masuk. Baik oleh rekanrekan seagamanya yang hidup di dunia mayoritas Muslim maupun minoritas Muslim yang hidup di negara-negara mayoritas non-Muslim di seluruh dunia. Kalau tidak dibuka dengan menggunakan kunci yang tepat, maka pintu tidak akan terbuka atau terbuka tetapi rusak. Baik dalam kondisi pintu tertutup maupun pintu rusak, keduanya akan berakibat kepada nasib umat Islam di seluruh dunia di era globalisasi seperti saat sekarang ini. Begitu kira-kira, kalau saya ingin membahasakan ulang keprihatinan Jasser Auda. Ilustrasi ‘kunci’ pintu yang saya sebut di atas, dalam istilah filsafat Ilmu kontemporer adalah Approaches atau berbagai pendekatan. Richard C. Martin memberi judul bukunya Approaches to Islam in Religious Studies. Jasser Auda menggunakan istilah A Systems Approach dalam bukunya. Dalam bahasa keilmuan Islam tradisional biasa disebut al-Tariqah (Metode) sehingga sangat popular pembedaan antara al-Maddah (Materi) dan al-Tariqah (Metode). Lalu, dikenallah adagium al-Tariqah ahammu min al-Maddah (Metode pembelajaran lebih penting dari pada materi pembelajaran). Penekanan pada Approaches memang berbeda dari penekanan pada Methods, karena dalam Approaches diperlukan persyaratan yang lebih dari pada persyaratan yang biasa berlaku dalam Method. Dalam Approaches terkandung syarat yang tidak tertulis bahwa seseorang, baik guru, dosen, da’i dan leaders of influence yang lain harus bersedia melakukan penelitian (research) dan studi perbandingan (comparasion) dengan cara melibatkan berbagai dan lintas disiplin ilmu (multi dan transdisciplin) dan pengalaman-pengalaman bidang lain, Bab 4 175 termasuk mengenal budaya setempat-lokal dan budaya globalinternasional (Urf) untuk mampu melakukan perbaikan, pembaharuan dan inovasi, Begitu juga bidang hukum Islam dan bidang-bidang ilmu keislaman yang lain, persyaratan tersebut berlaku sepenuhnya. Paradigma profetik dalam hukum Islam kontemporer, setidaknya, mencakup 2 (dua) Approaches yang perlu dikuasi sekaligus secara profesional, yaitu pertama, Approaches yang berhubungan erat dengan dimensi waktu dan kesejarahan (history) dan kedua, Approaches yang berhubungan erat dengan konsep dan pemikiran kefilsafatan (thought). Dalam hal yang terkait dengan dimensi waktu dan kesejarahan, ada 3 (tiga) lapis kunci pintu untuk mempelajari dan menganalisis pemikiran hukum Islam tradisional dalam upaya untuk membuka pintu ijtihad kontemporer, yaitu kunci pintu teori hukum era tradisional, kunci pintu teori hukum era modern dan terakhir adalah kunci pintu teori hukum era post modern. 16 Dengan menggunakan metode perbandingan pemikiran hukum Islam yang teliti, ketiga kunci pintu pisau bedah analisis pemikiran hukum tersebut digunakan oleh Jasser Auda untuk membuka horison dan kemungkinan membangun bangunan epistemologi keilmuan Islam baru di era kontemporer yang lebih bercorak profetis dan pro-etis dalam menghadapi guncangan arus globalisasi. Berbeda dari teori Postmodernism yang biasa digunakan oleh para pemikir Muslim kontemporer, Jasser Auda lebih menekankan pada aspek pendekatan atau Approaches yang lebih bersifat ‘multi-dimensional” (Multi-dimensional) dan pendekatan yang lebih utuh-menyeluruh (Holistic approach).17 Jika diskusi tentang hukum Islam di dunia Islam pada umumnya berkisar pada isu Syari’ah, Usul al-Fqh dan Fiqh, maka Jasser Auda mengambil jalan lain. Dia tetap menekankan pentingnya ketiga isu penting tersebut, tetapi dia menggeser paradigma pendekatannya lewat pintu masuk Maqasid yang diperbaharui. Tidak hanya teori, metode dan Jasser Auda. 2008. Maqasiid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, London dan Washington: The International Institute of Islamic Thought. Hlm.253. 17 Ibid. Hlm. l91. 16 176 Landasan Epistemologi... pendekatan fiqh Tradisonal dan fiqh Modern yang ia cermati dan gunakan, tetapi juga teori, metode dan pendekatan fiqh Postmodern juga ia gunakan, dengan dibarengi beberapa catatan kritis sudah barang tentu. Maqasid menjadi pangkal tolak berpikir untuk pengembangan pemikiran hukum Islam yang berparadigma profetik di era kontemporer dan di tengah gelombang besar globalisasi. Bukunya yang berjudul Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach merupakan pesan yang jelas-tegas bagaimana ide pembaharuan hukum Islam dan epistemologinya perlu dirumuskan kembali dan kemana hendak dituju. Teori Maqasid sebenarnya bukanlah barang baru dalam dunia berpikir hukum Islam. Kulliyyat al-Khams nya al-Syatibi sangatlah popular di dunia Usul al-Fiqh dan Fiqh dalam pemikiran hukum Islam. Tapi, Jasser Auda mengajukan pertanyaan penting yang ditujukan ke umat Islam yang hidup di era sekarang ini. Jika Kulliyyat al-Khams al-Syatibi itu memang penting dan fungsional di era kontemporer saat ini, mengapa dalam dunia kenyataan sehari-hari di negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim justru masih serba kekurangan, tertinggal dari negaranegara lain yang dulunya juga sama-sama kekurangan dan cenderung abai pada sisi moralitas, asas kepatutatan dan etika kemanusiaan. Laporan tahunan United Nation Development Programme (UNDP) menyebutkan bahwa Human Development Index (HDI) negara-negara yang berpenduduk Muslim masih rendah. Rendah dalam tingkat literasi (Literacy), tingkat pendidikan (Education), partisipasi politik dan ekonomi, pemberdayaan wanita (women empowerment), belum lagi menyebut standar dan kualitas kehidupan yang layak. Pertanyaan kedua yang diajukannya adalah mengapa justru di negara-negara berpenduduk Muslim yang income per capita nya cukup tinggi, justru tingkat keadilan, pemberdayaan wanita, partisipasi politik, dan kesempatan yang sama untuk semua warganegaranya malah rendah.18 What went wrong? Apa Ibid. Hlm. XXII. Ketika tulisan ini disiapkan, peristiwa penumbangan rejim pemerintah yang berkuasa lebih dari 30 tahun sedang berlangsung. Setelah Tunisia, gerakan rakyat menular ke Mesir dan berhasil pula menumbangkan pemerintahan Husni 18 Bab 4 177 yang salah dalam hal ini semua? Bisakah kita mengkritisi kembali bangunan epistemologi keilmuan Islam di bidang hukum Islam ini dan bagaimana implikasinya dalam wilayah pendidikan hukum?19 Tugas yang tidak mudah, karena asas dan prinsip dasar Kulliyat al-Kahms tersebut telah mengakar, mendarah dan mendaging, alias membudaya dalam pola pikir umat Islam dimana pun mereka berada sehingga sangat sulit untuk dikritisi dan dirumuskan ulang. Pola pikir atau worldview keagamaan ini telah menjadi preunderstanding dan bahkan menjadi affective history nya umat Islam dimanapun mereka berada, khususnya di wilayah Timur Tengah. Akan sangat sulit sekali merubahnya. Itulah batu karang budaya yang dihadapi oleh Jasser Auda dan dicoba untuk diurainya kembali asal-usul, perubahan dan perkembangannya lewat pendekatan Systems. a. Pendekatan waktu dan kesejarahan. Langkah dan pendekatan (approach) pertama yang dilakukan adalah membuat peta sejarah perkembangan pemikiran hukum Islam dengan teliti, mulai dari era Islam Tradisional, Islam Modern sampai Islam Postmodern. Dengan membaca dan meneliti literatur yang melintasi tiga jaman tersebut, ditemukan varian-varian pola pemikiran epistemologi keilmuan hukum Islam dan implikasinya dalam membentuk sikap etis yang berbeda-beda untuk masing-masing tahapan sejarah tadi. Pertama, Islamic Traditionalism. Ada 4 varian disini. 1) Scholastic Traditionalism, dengan ciri berpegang teguh pada salah satu madhhab fiqh tradisional sebagai sumber hukum tertinggi dan hanya membolehkan ijtihad, ketika sudah tidak ada lagi ketentuan hukum pada madhhab yang dianut. 2) Mubarak. Secara berturut-turut pindah ke Libia, Yaman, Bahrain dan yang masih terus bergejolak adalah Syuriah, dan begitu setrusnya. Sejarah Timur Tengah yang baru paska tumbangnya rejim yang otoriter sedang sedang dicari rumusannya. 19 Untuk wilayah pendidikan Islam, dapat diperbandingkan dengan pengamatan dan analisis Ibrahim M. Abu-Rabi’ terhadap praktik pendidkan Islam di dunia Muslim dalam artikelnya, “A Post-September 11 Critical Assesment of Modern Islamic History” dalam Ian Markham dan Ibrahim M. Abu Rabi’ (Ed.), 11 September: Raligious Perspectives on the Causes and Consequences, Oxford, Oneworld Publications, 2002, Hlm. 19-52. 178 Landasan Epistemologi... Scholastic Neo-Traditionalism, bersikap terbuka terhadap lebih dari satu madhab untuk dijadikan referensi terkait suatu hukum, dan tidak terbatas pada satu madhab saja. Ada beberapa jenis sikap terbuka yang diterapkan, mulai dari sikap terhadap seluruh madhab fiqh dalam Islam, hingga sikap terbuka pada madhab Sunni atau Shia saja. 3) Neo-Literalism, kecenderungan ini berbeda dengan aliran literalism klasik (yaitu mazhab Zahiri). Neo-literalism ini terjadi pada Sunni maupun Shia. Perbedaannya dengan literalism lama adalah jika literalism klasik (seperti versi Ibn Hazm) dengan neo-Literalism adalah literalism klasik lebih terbuka pada berbagai koleksi hadis, sedangkan neo-literalism hanya bergantung pada koleksi hadis dalam satu mazhab tertentu. Namun demikian, neo-literalism ini seide dengan literalisme klasik dalam hal sama-sama menolak ide untuk memasukkan purpose atau maqasid sebagai sumber hukum yang sah (legitimate). Contoh neo-literalism saat ini adalah aliran Wahabi. 4) Ideology-Oriented Theories. Ini adalah aliran traditionalism yang paling dekat dengan post-modernism dalam hal mengkritik modern ‘rationality’ dan nilai-nilai yang bias ‘euro-centricity’, ‘west-centricity’. Salah satu sikap aliran ini adalah penolakan mereka terhadap demokrasi dan sistem demokrasi, karena dinilai bertentangan secara fundamental dengan sistem Islam.20 Kedua, Islamic Modernism. Ciri umum para tokoh corak pemikiran ini adalah mengintegrasikan pendidikan Islam dan Barat yang mereka peroleh, untuk diramu menjadi tawaran baru bagi reformasi Islam dan penafsiran kembali (re-interpretation). Ada 5 varian disini. 1) Reformist Reinterpretation. Dikenal juga sebagai ‘contextual exegesis school’ atau atau menggunakan istilah Fazlur Rahman ‘systematic interpretation’. Contoh, Muhammad Abduh, Rashid Rida dan al-Tahir Ibn Ashur telah memberi kontribusi berupa mazhab tafsir baru yang koheren dengan sains modern dan rasionalitas. 2) Apologetic Reinterpretation. Perbedaan antara reformist reinterpretations dan apologetic reinterpretations adalah reformist memiliki tujuan untuk membuat perubahan nyata dalam implementasi hukum Islam praktis; sedangkan apologetic lebih pada menjustifikasi status quo 20 Untuk lebih detil, lebih lanjut Jasser Auda, Ibid. Hlm. l62-l68. Bab 4 179 tertentu, ‘Islamic’ atau ‘non-Islamic’. Biasanya didasarkan pada orientasi politik tertentu. Contoh seperti Ali Abdul Raziq dan Mahmoed Mohammad Taha. 3) Dialogue-Oriented Reinterpretation / Science-Oriented Reinterpretation. Ini merupakan aliran modernis yang menggunakan pendekatan baru untuk reinterpretasi. Mereka memperkenalkan ‘a scientific interpretation of the Qur’an and Sunnah’. Dalam pendekatan ini, ‘rationality’ didasarkan pada ‘science’, sedangkan ayat-ayat al-Qur’an maupun hadis direinterpretasi agar selaras dengan penemuan sains terbaru. 4) Interest-Oriented Theories. A Maslahah-based approach ini berusaha untuk menghindari kelemahan sikap apologetic, dengan cara melakukan pembacaan terhadap nass, dengan penekanan pada maslahah yang hendak dicapai. Contoh, seperti Mohammad Abduh dan al-Tahir ibn Ashur yang menaruh perhatian khusus pada maslahah dan maqasid dalam hukum Islam, sehingga mereka menginginkan reformasi dan revitalisasi terhadap hukum Islam yang terfokus pada metodologi baru yang berbasis maqasid. 5) Usul Revision. Tendensi ini berusaha untuk merevisi Usul al-Fiqh, mengesampingkan keberatan dari neo-tradisionalis maupun fundamentalist lainnya. Bahkan para tokoh yang tergolong Usul Revisionist menyatakan bahwa ‘tidak ada pengembangan signifikan dalam hukum Islam yang dapat terwujud, tanpa mengembangkan Usul a-Fiqh dari hukum Islam itu sendiri.21 Beberapa nama disebut sebagai contoh, antara lain Mohammad Abduh (1849-l905), Mohammad Iqbal (1877-1938), Rashid Rida, al-Tahir ibn Ashur, al-Tabtabai, Ayatullah al-Sadir, Mohammad al-Ghazali, Hasan al-Turabi, Fazlur Rahman, Abdullah Draz, Sayyid Qutb, Fathi Osman . Juga Ali Abdul Raziq, Abdulaziz Sachedina, Rashid Ghannouchi, Mohammad Khatami. Ketiga, Post-modernism. Metode umum yang digunakan tendensi ini adalah ‘deconstruction’, dalam style Derrida. Ada ada 6 varian di sini. 1) Post Structuralism. Berusaha membebaskan masyarakat dari otoritas nass dan menerapkan teori semiotic ( Teori yang menjelaskan bahwa “Bahasa sesungguhnya tidak menunjuk kepada realitas secara langsung’ 21 Untuk lebih detil, lebih lanjut Jasser Auda, Ibid. Hlm. 168-180. Landasan Epistemologi... 180 (Language does not refer directly to the reality) terhadap teks al-Qur’an agar dapat memisahkan bentuk implikasi yang tersirat (separate the implication from the implied). 2) Historicism. Menilai al-Qur’an dan hadis sebagai ‘cultural products’ dan menyarankan agar deklarasi hak-hak asasi manusia modern dijadikan sebagai sumber etika dan legislasi hukum.3) Critical –Legal Studies (CLS). Bertujuan untuk mendekonstruksi posisi ‘power’ yang selama ini mempengaruhi hukum Islam, seperti powerful suku Arab dan “male elitism’. 4) Post-Colonialism. Mengkritik pendekatan para orientalis klasik terhadap hukum Islam, serta menyerukan pada pendekatan baru yang tidak berdasarkan pada ‘essentialist fallacies’ (prejudices) terhadap kebudayaan Islam. 5) Neo-Rationalism. Menggunakan pendekatan historis terhadap hukum Islam dan mengacu pada madhhab mu’tazilah dalam hal rational reference untuk mendukung pemahaman mereka. Banyak nama yang disebut. Antara lain Mohammad Arkoun, Nasr Hamid Abu Zaid, Hasan Hanafi, al-Tahir al-Haddad dan juga Ebrahim Moosa dengan buku-buku atau artikel yang disebut dalam bab Bibliograpi. Juga Ayatullah Shamsuddin, Fathi Osman, Abdul Karim Soroush, Mohammad Shahrur dan yang lain-lain.22 Dengan mencermati seluruh metode dan pendekatan yang digunakan oleh para pemikir hukum Islam , yang dipetakannya menjadi Tradisionalisme, Modernisme dan Postmodernisme, Jasser Auda kemudian mengajukan pendekatan Systems untuk membangun kerangka pikir baru untuk pengembangan hukum Islam di era globalkontemporer. Hasil penelitian terhadap ke tiga trend hukum Islam diatas dinyatakan sebagai berikut : Current applications ( or rather, mis-applications) of Islamic Law are reductionist rather than holistic, literal rather than moral, one-dimensional rather than multidimensional, binary rather than multi-valued, deconstructionist rather than reconstructionist, and causal rather than teleological.23 (Penerapan - atau lebih tepat disebut kesalah-penerapan - hukum Islam di era sekarang adalah karena penerapannya lebih bersifat reduktif (tidak 22 23 Ibid. Hlm. 180-191. Ibid. Hlm. xxvii Bab 4 181 utuh) dari pada utuh, lebih menekankan makna literal dari pada moral, lebih terfokus pada satu dimensi saja dari pada multidimensi, nilainilai yang dijunjung tinggi lebih bercorak hitam-putih dari pada warnawarni pelangi, bercorak dekonstruktif dari pada rekonstruktif, kausalitas dari pada berorientasi pada tujuan (teleologis). Penggunaan pendekatan Systems yang ia usulkan berupaya keras untuk menghidari dan menghilangkan sedapat mungkin kekurangan-kekurangan yang disebut tadi. Pendekatan Systems yang ia usulkan lebih mengarah pada pembentukan paradigma profetik dalam hukum Islam kontemporer. b. Pendekatan Systems dalam Hukum Islam. Apa yang dimaksud dengan pendekatan Systems? Sistem adalah disiplin baru yang independen, yang melibatkan sejumlah dan berbagai sub-disiplin. Teori Systems dan Analisis Sistematik adalah bagian tak terpisahkan dari tata kerja pendekatan Systems. Teori Systems adalah jenis lain dari pendekatan filsafat yang bercorak ‘anti-modernism’ (anti modernitas) yang mengkritik modernitas dengan cara yang berbeda dari cara yang biasa digunakan oleh teori-teori postmodernitas. Konsep-konsep dasar yang biasa digunakan dalam pendekatan dan analisis Systems antara lain adalah melihat persoalan secara utuh (Wholeness), selalu terbuka terhadap berbagai kemungkinan perbaikan dan penyempurnaan (Openness), salingketerkaitan antar nilai-nilai (Interrelated-Hierarchy), melibatkan berbagai dimensi (Multidimensionality) dan mengutamakan dan mendahulukan tujuan pokok (Purposefulness). Masih terkait dengan Systems sebagai disiplin baru adalah apa yang disebut dengan Cognitive science, yakni bahwa setiap konsep keilmuan apapun - keilmuan agama maupun non-agama - selalu melibatkan intervensi atau campur tangan kognisi manusia (Cognition). Konsep-konsep seperti klasifikasi atau kategorisasi serta watak kognitif (cognitive nature) dari hukum akan digunakan untuk mengembangkan konsep-konsep fundamental dari teori hukum Islam.24 24 Ibid. Hlm. xxvi. 182 Landasan Epistemologi... Jasser Auda menggunakan teori, pendekatan dan analisis Systems untuk merumuskan kembali dan membangun epistemologi hukum Islam di era global yang lebih berbobot pro(f)etik setelah dengan cermat mengulas tiga tahapan sejarah panjang pemikiran hukum Islam seperti telah diuraikan diatas. Ditegaskan lagi bahwa tanpa melibatkan dan menggunakan ide-ide dan pikiran-pikiran yang relevan dari disiplin ilmu yang lain, seperti sosiologi, antropologi, psikologi, komukinasi dan sains pada umumnya, maka penelitian yang terkait dengan teori fundamental hukum Islam akan tetap ‘terjebak’ dalam batas-batas literatur-literatur tradisional berikut manuskrip-manuskripnya, dan hukum Islam akan terus menerus “tertinggal” (outdated) dalam membangun basis teorinya dan parktik-praktik pelaksanaan hukum di lapangan , dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat multikultutal seperti di era global sekarang ini. Oleh karenanya, relevansi dan kebutuhan untuk menggunakan pendekatan multidisiplin, interdisiplin, bahkan transdisiplin untuk merespon isu-isu fundamental dalam hukum Islam di era kontemporer sangat digarisbawahi oleh Jasser Auda. Akan disinggung secara singkat 6 fitur epistemologi hukum Islam kontemporer, yang menggunakan pendekatan Systems. 6 fitur ini dimaksudkan untuk mengukur dan sekaligus menjawab pertanyaan bagaimana Maqasid al-Syari’ah diperankan secara nyata dalam metode pengambilan hukum dalam berijtihad di era sekarang. Bagaimana kita dapat menggunakan Filsafat Systems Islam (Islamic Systems Philosophy) dalam teori dan praktik yuridis, agar supaya hukum Islam tetap dapat diperbaharui (renewable) dan hidup (alive)? Bagaimana pendekatan Systems yang melibatkan cognition, holism, openness, interrelated hierarchy dan multidimensionality dan purposefulness dapat diaplikasikan dan dipraktikkan dalam teori hokum Islam dan pendidikan hukum pada umumnya? Bagaimana kita dapat menemukan kekurangan-kekurangan yang melekat pada teori-teori Klasik (Tradisional), Modern dan Post-modern dalam hukum Islam dan berupaya untuk menyempurnakan dan memperbaikinya? Secara intelektual, upaya ini sangat penting karena Bab 4 183 keberhasilan dan kegagalannya akan berpengaruh secara langsung terhadap bangunan materi pendidikan dan pengajaran di setiap lapis dan jenjangnya, rumusan teori, metode dan pendekatan yang biasa berlaku dan digunakan dalam pendidikan Islam, dakwah Islam, politik, ekonomi, budaya dan sosial masyarakat Muslim dimanapun mereka berada, baik untuk mayoritas Muslim di dunia bagian Timur maupun minoritas Muslim di Barat 1) Kognisi (Cognitive nature) dari Islam. hukum Berdasarkan perspektif teologi Islam, fiqh adalah hasil penalaran dan refleksi (ijtihad) manusia terhadap nass (teks kitab suci) sebagai upaya untuk menangkap makna tersembunyi maupun implikasi praktisnya. Para ahli fiqh maupun kalam (Mutakallimun) bersepakat bahwa Allah tidak boleh disebut sebagai faqih (jurist atau lawyer), karena tidak ada yang tersembunyi bagi-Nya. Oleh karena itu, fiqh merupakan bagian dari kognisi manusia atau a matter of human cognition (idrak) dan pemahaman (fahm). Meminjam istilah yang digunakan Ibn Taimiyyah, bahwasanya hukum fiqh selama ini adalah merupakan pemahaman atau hasil bentukan kognisi dari para ahli agama atau fuqaha (fii dzihni alfaqih). Dengan demikian, sangat dimungkinkan memiliki kelemahan dan kekurangan. Dalam khazanah filsafat ilmu kontemporer, hal-hal yang terkait dengan isu ini dikenal dengan istilah the fallibility atau the corrigibility of knowledge25 ( ilmu pengetahuan apapun, termasuk di dalamnya Dalam pengamatan saya, sudah barang tentu belum tentu benar, karena masih harus dibuktikan dengan penelitian yang mendalam di lapangan bahwasanya mata kuliah dan diskusi filsafat ilmu di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), apalagi di lingkungan di Perguruan Tinggi Umam (PTU) belum pernah bersentuhan dengan ilmuilmu agama (Islam). Alasan yang biasa diungkapkan oleh para dosen filsafat ilmu karena mereka tidak mengenal apalagi menguasai ilmu-ilmu keagamaan Islam. Dan begitu pula sebaliknya. Para dosen agama di Perguruan Tinggi Agama maupun Umum tidak mengenal dengan baik dan profesional tentang filsafat ilmu, lebih-lebih filsafat ilmu yang dikaitkan dengan diskusi keagamaan. Tentang konsep The corrigibility of knowledege, lihat Milton K. Munitz. 1981. Contemporary Analytic Philosophy, New York: MacMillan Publishing CO. Inc. Hlm. 31-34. 25 184 Landasan Epistemologi... konsepsi dan teori keilmuan keagamaan yang disusun oleh para cerdik pandai (fuqaha; ulama) dapat saja mengalami kesalahan dan ketidaktepatan). Sebagai konsekwensinya, pemahaman fiqh pada era tertentu, tingkat capaian pendidikan dan tingkat literasi manusia era tertentu serta perkembangan ilmu pengetahuan era tertentu dapat diperdebatkan dan dapat diubah (qabilun li al-niqasy wa al-taghyir) ke arah yang tepat dan lebih baik, kata Mohammad Arkoun, seperti yang sering saya kutip dalam berbagai tulisan saya. Gambaran atau fitur cognitive nature of Islamic Law ini penting untuk memvalidasi kebutuhan terhadap suatu pemahaman yang pluralistik bagi seluruh madhhab fiqh, sekaligus untuk menghidari truth-claims yang berlebihan dalam beragama.26 Dengan demikian, Fiqh merupakan persepsi dan interpretasi seseorang yang bersifat ‘subjektif’. ‘Subjektif’ disini tidak saja berarti hanya terbatas pada ‘individu-individu’, tetapi terlebih-lebih lagi adalah ‘kelompok’, ‘golongan’, ‘mazhab’, organisasi sosial keagamaan, untuk tidak menyebut seluruh al-firaq al-Islamiyyah (berbagai kelompok yang hidup di lingkungan internal kehidupan umat Islam). Sayangnya, metode ijtihad fiqh dan hasilnya seringkali dipersepsikan oleh umat Muslim sebagai ‘aturan Tuhan’ yang tidak bisa diganggu gugat. Bangunan epistemologi Muslim Tradisional sangat sulit memahami dan membedakan bahwasanya ayat-ayat al-Qur’an adalah wahyu, tetapi interpretasi ulama atau faqih terhadap ayat-ayat tersebut bukanlah wahyu. Persepsi yang keliru ini seringkali memang dengan sengaja dipelihara dan dikukuhkan, demi melestarikan berbagai kepentingan sedikit orang, pemimpin atau organisasi yang “kuat” tertentu.27 Jasser Auda memberi contoh tentang ijma’ (consensus). Meskipun terdapat perbedaan besar atas berbagai keputusan ijma’, namun sebagai ulama fiqh menyebutnya sebagai dalil qat’i (dalil yang pasti) yang setara dengan nass (Dalilun Qat’iyyun ka al-Nass), dalil dibuat oleh pembuat syari’at (dalilun nassabah al-Syari’), dan bahkan penolak ijma’ adalah kafir (jahid 26 27 Jasser Auda, Op.Cit. Hlm. 46. Jasser Auda, Op.Cit. Hlm. l93. Bab 4 185 al-ijma’ kafir). Pembaca yang familiar dengan literatur fiqh klasik/ tradisional akan mengetahui bahwa ijma’ sering dijadikan klaim untuk menghakimi opini atau pendapat orang lain yang berbeda. Ibn Taimiyyah sebagai contoh, mengkritik buku kumpulan ijma’ (Maratib al-Ijma’) Ibn Hazm. Dikatakan bahwa klaim perkara-perkara yang sudah diijma’kan dalam kitab tersebut tidaklah akurat, sebab persoalannya sendiri masih menjadi masalah khilafiyyah (perbedaaan pendapat). Seperti persoalan menolak ijma’ dianggap kafir, persoalan tidak ikutnya perempuan dalam salat jamaahnya laki-laki, dan penyelenggaraan pembayaran empat dinar emas sebagai jizyah (pajak).28 Berbeda dari pandangan diatas, Jasser Auda berpendapat bahwa Ijma’ bukan merupakan sebuah sumber hukum, akan tetapi hanya sebuah mekanisme pertimbangan atau sistem pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh banyak pihak. Oleh karena itu, Ijma’ sering disalahgunakan oleh sebagian ulama untuk memonopoli fatwa demi kepentingan sekelompok “elite”. Sampai sekarang, prinsip-prinsip itu masih sangat mungkin dipakai sebagai mekanisme untuk membuat fatwa yang bersifat kolektif, khususnya persoalan yang terkait dengan teknologi modern dan dengan cara memanfaatkan telekomunikasi yang sangat cepat. Ijma’ juga dapat dikembangkan dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam memutuskan kebijakan pemerintah.29 2). Utuh (Wholeness; saling terkait antar berbagai komponen atau unit yang ada). Salah satu faktor yang mendorong Jasser Auda menganggap penting komponen wholeness dalam pendekatan Systemsnya adalah pengamatannya terhadap adanya kecenderungan beberapa ahli hukum Islam untuk membatasi pendekatan berpikirnya pada pendekatan yang bersifat reduksionistic dan atomistic, yang umum digunakan dalam Usul al Fiqh. Para ahli Usul al-Fiqh terdahulu, khususnya al-Razi, telah menyadari hal itu. Hanya saja, kritik al-Razi kepada kecenderungan atomistic ini hanya 28 29 Jasser Auda, Op. cit. Jasser Auda, Op.Cit. Hlm. l93-l94. 186 Landasan Epistemologi... didasarkan pada adanya unsur ketidakpastian (uncertainty) sebagai hal yang berlawanan secara biner dengan kepastian (certainty) dalam pemikiran fiqh, tetapi belum sampai masuk ke persoalan ketidakpastian dalil tunggal yang didasarkan atas parsialitas dan atomisitas yang melatarbelakangi cara berpikir kausalitas.30 Sedangkan pada era sekarang ini, penelitian di bidang ilmu alam dan sosial telah bergeser secara luas dari ‘piecemeal analysis’, classic equations dan logical statements, menuju pada penjelasan seluruh fenomena dalam istilah-istilah yang bersifat holistic sistem. Bahkan dalam fenomena fisik yang mendasar, seperti ruang/waktu dan badan (body)/pikiran (mind), tidak dapat dipisahkan secara empiris, menurut ilmu masa kini. Teori Systems berpendapat bahwa setiap hubungan ‘sebab dan akibat’ hanyalah sebagai salah satu bagian dari keutuhan gambaran tentang realitas, dimana sejumlah hubungan akan menghasilkan properti baru yang muncul dan kemudian bergabung membentuk keutuhan (whole) yang lebih dari sekedar kumpulan dari bagian-bagian (sum of the parts). Menurut argumen teologi dan ‘rasional’, hujjiyyah (juridical authority) yang termasuk ‘the holistic evidence’ (al-dalil al-kulliy) dinilai sebagai salah satu bagian dari Usul al Fiqh yang menurut para ahli fiqh (jurists), posisinya lebih unggul dibandingkan hukum yang bersifat tunggal dan parsial (single and partial rulings).31 Memasukkan pola dan tata berpikir holistik dan sistematik ke dalam dasar-dasar pemahaman hukum Islam (Usul al-Fiqh) akan sangat bermanfaat bagi filsafat Islam tentang hukum (Islamic philosophy of law) agar mampu mengembangkan horison berpikir dari yang semula hanya berdasar pada logika bahasa sebab-akibat (‘illah) ke arah horison berpikir yang lebih holistic, yaitu pola pikir yang mampu mempertimbangkan, menjangkau dan mencakup hal-hal lain yang tidak atau belum terpikirkan di luar proses berpikir sebab-akibat. Para ahli Usul Fiqh terdahulu, seperti Fakhr al-Din al-Razi, telah mengingatkan dari dulu adanya kesulitan ini. Setidaknya ada 9 sebab yang mendasari al-Razi berpendapat bahwa bukti yang berdasarkan pada bahasa (linguistic evidence/Dalil al Khitab) dari sebuah nass hanyalah bersifat probable (zanni). Lebih lanjut Jasser Auda, ibid. Hlm. l97-8. 31 Jasser Auda, Ibid. Hlm. 46-7. 30 Bab 4 187 Pendekatan holistic juga bermanfaat untuk Ilmu Kalam agar dapat mengembangkan pola pikir bahasa kausalitasnya (cause and effect) ke arah pola pikir yang lebih sistematic, termasuk bukti-bukti tentang keberadaan Tuhan. Implikasi penggunaan fitur wholeness dalam berpikir keagamaan Islam adalah seseorang harus memahami nass (al-Qur’an maupun Hadis) secara lebih utuh, baik yang bersifat juz’i (part) maupun kully (whole) secara bersama-sama. Sebagai contoh memahami hukum poligami tidak cukup lagi hanya dengan mengutip satu ayat saja (Surat al-Nisa’, 3), melainkan juga harus membandingkan dengan keseluruhan ayat al-Qur’an yang lain yang memiliki relevansi dengan hukum poligami (seperti al-Nisa’, 129). 32 Dalam hal ini, seorang dapat memanfaatkan metode maudlu’i atau biasa disebut dengan tafsir tematik agar mendapatkan pemahaman yang ‘relatif’ lebih utuh dalam memahami ayat-ayat al-Qur’an.33 Disebutkan dalam al-Qur’an, surat al-Nisa’, ayat 3 sebagai berikut: “ Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya’ Sedang surat al-Nisa’ ayat 129 sebagai berikut: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. Terjemahan al-Qur’an diambil dari Al-Qur’an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, cetak hitam dari penulis. 33 Ketika menulis draft tulisan pada bagian ini, saya lalu teringat ketika diberi amanat mengetuai Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, PP Muhammadiyah, antara tahun 1995-2000. Ketika itu, saya mengusulkan perlunya penulisan tafsir tematik alQur’an, dengan beberapa tema. Atas usulan anggota Majlis, yang pertama diprioritaskan saat itu adalah tafsir tematik yang membahas Hubungan Sosial Antarumat Beragama. Kemudian ditulislah secara kolektif (melibatkan beberapa penulis), dan saya sendiri tidak ikut menulis tetapi ikut member masukan disana sini. Dengan persetujuan Pimpinan Pusat terbitlah tafsir tersebut dengan judul Tafsir Tematik al-Qur’an tentang Hubungan Sosial Antarumat Beragama, Yogyakarta, Pusataka SM, 2000. Kabarnya, buku tafsir tersebut tidak dicetak lagi, karena adanya keberatan dari sebagian anggota persyarikatan dengan alasan prosedur birokrasi keorganisasian. 32 188 Landasan Epistemologi... Para modernis Muslim akhir-akhir ini mengintrodusir aplikasi yang signifikan tentang prinsip holistik ini. Tafsir Hasan Turabi, misalnya, yang berjudul Tafsir al-Tauhidy jelas-jelas memperlihatkan pendekatan holisme. Turabi menguraikan bahwa pendekatan kesatuan (tauhidy) atau holistic (kully) memerlukan sejumlah metodologi pada level yang berbeda-beda dan beragam. Pada level bahasa membutuhkan hubungan dengan bahasa al-Qur’an ketika bahasa penerima pesan-pesan al-Qur’an pada waktu wahyu diturunkan. Pada level pengetahuan manusia membutuhkan sebuah pendekatan holistic untuk memahami dunia yang terlihat dan yang tidak terlihat dengan seluruh jumlah komponen yang banyak. Pada level topik membutuhkan hubungan dengan tema-tema tanpa memperhatikan tananan dan urut-urutan wahyu, selain untuk menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Dalam bahasan ini termasuk membicarakan orang-orang yang tanpa memperhatikan ruang dan waktu. Ini juga membutuhkan kesatuan hukum dengan moralitas dan spititualitas dalam satu pendekatan yang holistitik. 3). Openness (Self-Renewal). Teori Systems membedakan antara sistem ‘terbuka’ dan sistem ‘tertutup’. Sistem yang hidup adalah sistem yang terbuka. Ini berlaku untuk organisme yang hidup, juga berlaku pada sistem apapun yang ingin survive (bertahan hidup). Sistem dalam hukum Islam adalah sistem yang terbuka (open system). Seluruh mazhab dan mayoritas ahli fiqh selama berabad-abad telah setuju bahwa ijtihad itu sangat penting bagi hukum Islam, karena nass itu sifatnya terbatas, sedangkan peristiwaperistiwa itu tidak terbatas ( al-Nusus mutanahiyah wa al-waqai’ ghairu mutanahiyah; specific scripts are limited and events are unlimited). Akhirnya, metodologi Usul al-Fiqh mengembangkan mekanisme tertentu untuk menghadapi kasus-kasus baru yang ditemui ketika berinteraksi dengan lingkungan. Mekanisme Qiyas, Maslahah dan mengakomodasi tradisi (i’tibar al-urf) adalah beberapa contohnya. Mekanisme-mekanisme seperti itu perlu lebih dikembangkan lagi dalam rangka memberi ruang fleksibilitas atau ruang gerak yang lebih elastis bagi hukum Islam atau Bab 4 189 fiqh agar dapat menghadapi lingkungan pada masa kini yang terus berubah secara cepat. Masalah yang dihadapi minoritas Muslim di Barat adalah sangat berbeda dari masalah yang dihadapi mayoritas Muslim di negara-negara berpenduduk Muslim mayoritas di Timur, misalnya. Oleh karenanya mekanisme dan tingkat keterbukaan ini merupakan fitur penting dan berguna untuk mengembangkan dan menganalisis secara kritis terhadap bangunan sistem berpikir Usul alFiqh maupun sub-sub sistem yang berada dibawahnya. Mekanisme Openness dan Self-renewal dalam hukum Islam sangat tergantung kepada dua hal, yaitu perubahan pandangan keagamaan para ahli hukum agama atau budaya berpikir mereka (cognitive culture) dan keterbukaan filosofis (Philosophical openness). Pertama, Cognitive culture. Cognitive culture adalah kerangka berpikir serta pemahaman manusia atas realitas. Dengan kerangka pikir tersebut manusia melihat dan berhubungan dengan dunia luar. Sebenarnya, istilah al-urf dalam teori hukum Islam, terkait erat dengan urusan bagaimana ‘hubungan dengan dunia luar’. Maksud yang terkandung di belakang perlunya mempertimbangan urf dalam hukum Islam adalah sebagai cara untuk mengakomodasi atau menerima lingkungan dan adat istiadat masyarakat yang berbeda dari masyarakat dan adat istiadat Arab. Sayangnya, implikasi praktis dari teori urf ini sangat terbatas dalam pemikiran fiqh Islam. Banyak ahli hukum Islam yang tetap mengaitkannya hanya dengan adat istiadat Arab pada dua abad pertama atau ketiga sejarah Islam dan bahkan masih pada batas-batas wilayah politik, geograpi, makanan, sumber-sumber ekonomi, sistem sosial, dan pandangan dunia mereka saat itu.34 Pandangan hidup keagamaan Islam era kontemporer pastinya berbeda dari pandangan hidup keagamaan era abad-abad terdahulu. Ahli hukum agama era sekarang harus mempunyai kompetensi yang memadai dan dapat dipertanggungajwabkan secara sosial dan keilmuan. Salah satu yang perlu dimilikinya sekarang adalah mempunyai 34 Jasser Auda, Ibid. Hlm. 202. 190 Landasan Epistemologi... pandangan keilmuan yang luas, karena metode penelitian (scientific investigation) adalah bagian dari worldview seseorang atau kelompok era sekarang. Seorang ahli hukum yang tidak memiliki ‘competent worldview’ pastinya tidak berkompeten pula untuk membuat, merumuskan apalagi mengeluarkan putusan-putusan keagamaan atau fatwa-fatwa fiqh yang tepat. Dengan tegas, untuk meningkatkan kualitas kompetensi para ahli hukum Islam di era global sekarang, Jasser Auda mengusulkan dimasukkan dan dikuasainya ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial. Interaksi antara ilmu-ilmu hukum Islam dan ilmu-ilmu sosial dan ilmuilmu kealaman adalah merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar pada era sekarang. Semacam ini pulalah yang diusulkan oleh Abdullah Saeed ketika ia mengajukan istilah fresh ijtihad ketika umat Islam menghadapi isu-isu kontemporer. Putusan-putusan dan fatwafatwa keagamaan tentang tanda-tanda kematian, waktu kehamilan, masa pubertas, penentuan awal bulan ramadlan (hisab dan ru’yah wujud al-hilal), apalagi persoalan-persoalan sosial yang berat seperti pluralitas etnis, ras, kulit dan agama, multikulturalitas, hak asasi manusia, perlindungan anak dan wanita, kepemimpinan wanita di ruang publik, hubungan bertetangga yang baik dengan non-muslim dan begitu seterusnya tidak bisa dikeluarkan dengan begitu saja tanpa didahului dengan penelitian yang mendalam berpatokan dan berlandaskan pada metodologi yang tepat sesuai kesepakatan komunitas ilmuan ilmu-ilmu alam dan atau ilmu-ilmu sosial.35 Jasser Auda, Ibid. Hlm. 204-206. Tiba-tiba sekarang saya merasa mendapat dukungan moral dan basis landasan epistemologi keilmuan yang lebih kokoh, dibandingkan ketika saya menulis hal-hal seperti ini pada tahun l997/l998. Periksa tulisan saya ketika mengambil program posdoktoral di McGill, berjudul “Preliminary Remarks on the Philosophy of Islamic Religious Science”, Al-Jami’ah, No. 61, TH., 1998, h. 1-26. Tulisan ini saya susun khusus untuk mengantisipasi dan mempersiapkan konsep kerangka dasar keilmuan jika memang akan terjadi transformasi kelembagaan dan keilmuan dari IAIN ke UIN. Saat itu, IAIN Yogyakarta dan Jakarta memang sedang diminta BAPENAS untuk menyusun proposal ke Islamic Development Bank (IDB). Tulisan ini kemudian diterjemahkan ke Indonesia dengan judul “Pendekatan dalam Kajian Islam: Normatif atau Historis (Membangun Kerangka Dasar Filsafat Ilmi-ilmu Keislaman)”. Lihat M. Amin Abdullah, Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006, h. 26-67. 35 Bab 4 191 Kedua, Self-renewal lewat keterbukaan filosofis. Secara historis, tidak bisa dibantah bahwa mayoritas para sarjana Islam, khususnya yang terdidik lewat madhhab tradisional hukum Islam, menolak upaya apapun yang ingin menggunakan filsafat untuk mengembangkan hukum Islam atau keilmuan Islam pada umumnya. Banyak fatwa dikeluarkan melarang mempelajari dan mengajarkan filsafat pada dunia pendidikan Islam karena menurut mereka filsafat didasarkan pada sistem metapisika yang tidak Islami. Tuduhan murtad (apostasy) beredar dimana-mana. Fatwa-fatwa seperti itu keluar dari para ahli hukum Islam terkenal seperti Ibn Aqil (w. 1119 M), al-Nawawi (w. 1277 M), al-Sayuti (w. 1505 M), alQushairi (w. 1127 M), al-Sharbini (w. 1579 M) dan ibn Salah (w. l246 M). Tapi al-Ghazali (w. 1111 M), begitu juga al-Amidi (w. 1236 M) dan alSubki (w. 1374 M) mempunyai pendapat yang sedikit berbeda disini. Dia membedakan antara apa-apa yang dapat dipinjam dari non-Muslim (saat itu adalah tradisi keilmuan Yunani/Aristotle ), yaitu hal-hal yang terkait dengan bidang metodologi “abstract tools” dan apa yang tidak dapat dipinjam dari non-Muslim.36 Jasser Auda menambahkan bahwa cara berpikir seperti itu mirip-mirip dengan fatwa kontemporer yang dikeluarkan oleh Neo-Literalist yang membolehkan mengambil atau meniru ilmu pengetahuan dari Barat yang terkait dengan “teknologi”, tetapi tidak boleh mengambil apalagi meniru ilmu-ilmu dari Barat yang terkait dengan humanities dan ilmu-ilmu sosial.37 Jasser Auda menyayangkan mengapa para ahli teori hukum Islam tidak mengambil manfaat dari sumbangan yang genuine yang diberikan para filosof Muslim kepada filsafat Yunani, khususnya, logika sebagai ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, Ibn Sina (w. 1037 M) menyumbangkan konsep pemikiran yang orisinal terhadap logika dengan cara merekonstruksi kembali teori Aristotle tentang Silogisme setelah membedakan kasus-kasus yang melibatkan dimensi waktu yang berbeda Jasser Auda, Ibid. Hlm. 209. Bandingkan dengan footnote nomer 4 di atas. Jasser Auda, Op. cit., Bandingkan dengan pendapat Ibrahim M. Abu-Rabi’, pada footnote di atas. 36 37 192 Landasan Epistemologi... (time dependent). Sumbangan penambahan dimensi waktu terhadap standar derivasi silogistik Aristotle sangat dirasakan manfaatnya, dan sangat potensial untuk dimasukkan juga ke dalam struktur logika hukum Islam. Sumbangan orisinal lain yang diberikan oleh filosof Muslim tetapi tidak dimanfaatkan oleh para ahli hukum Islam adalah teori silogistik al-Farabi (w. 950 M) tentang argumentasi induktif. Cara berpikir induktif ini juga sangat penting untuk dimasukkan ke dalam cara berpikir hukum Islam. Sama halnya, kritik Ibn Hazm dan Ibn Taimiyyah terhadap logika Aristotle membuka babakan baru berkembangnya logika induktif J. S. Mill, namun sekali lagi hukum Islam tidak dapat mengambil manfaat dan tidak menggunakannya dalam bangunan dasar cara berpikirnya. Juga sumbangan Ibn Rusdh. Metode Ibn Rusdh dalam memadukan akal dan wahyu, keterbukaan kepada orang dan kelompok lain (the Other), penolakannya terhadap siapapun yang terburu-buru menuduh menyimpang atau murtad (heresy), dan ajakannya untuk menggunakan filsafat untuk memperbaharui dan membangun cara berpikir, semuanya mempunyai pengaruh yang besar terhadap gerakan pembaharuan dan modernism Islam pada abad yang lalu. Sayangnya, kata Jasser Auda, Ibn Rusdh sendiri tidak begitu mendiskusikan hubungan antara pandangan-pandangannya dalam filsafat dan pandangannya dalam hukum Islam. Di atas segalanya, agar hukum Islam dapat memperbaharui dirinya sendiri, adalah sangat perlu untuk mengadop sikap keterbukaan Ibn Rusdh terhadap semua penelitian filsafat (Philosophical investigation) dan memperluas jangkauan radius keterbukaaan ini ke wilayah teoriteori fundamantal hukum Islam atau Usul itu sendiri.38 4). Interrelated Hierarchy . Menurut ilmu Kognisi (Cognitive science), ada 2 alternasi teori penjelasan tentang kategorisasi yang dilakukan oleh manusia, yaitu ‘feature-based categorisations’ dan ‘concept-based categorisations’. Jasser Auda lebih memilih kategorisasi yang berdasarkan konsep untuk diterapkan pada 38 Jasser Auda, Ibid. Hlm. 210-11. Bab 4 193 Usul-al Fiqh. Kelebihan ‘concept-based categorisations’ adalah tergolong metode yang integrative dan sistematik. Selain itu, yang dimaksud ‘concept’ di sini tidak sekedar fitur benar atau salah, melainkan suatu kelompok yang memuat criteria multi-dimensi, yang dapat mengkreasikan sejumlah kategori secara simultan untuk sejumlah entitas-entitas yang sama.39 Salah satu implikasi dari fitur interrelated –hierarchy ini adalah baik daruriyyat, hajiyyat maupun tahsiniyyat, dinilai sama pentingnya. Lain halnya dengan klasifikasi al-Syatibi (yang menganut feature-based categorizations), sehingga hirarkhinya berifat kaku. Konsekwensinya, hajiyyat dan tahsiniyyat selalu tunduk kepada daruriyyat. Contoh penerapan fitur Interrelated – hierarchy adalah baik salat (daruriyyat), olah raga (hajiyyat) maupun rekreasi (tahsiniyyat) adalah sama-sama dinilai penting untuk dilakukan. 5). Multi-dimensionality. Dalam terminologi teori Systems, dimensionalitas memiliki dua sisi, yaitu ‘rank’ dan ‘level’. ‘Rank’ menunjuk pada sejumlah dimensi yang terkait dengan ‘ruang’, sedang ‘Level’ menunjuk pada sejumlah kemungkinan tingkatan atau ‘intensitas’ dalam satu dimensi. Cara berpikir pada umumnya dan berpikir keagamaan khususnya, seringkali dijumpai bahwa fenomena dan ide diungkapkan dengan istilah yang bersifat dikhotomis, bahkan berlawanan (opposite), seperti agama/ilmu, fisik/metafisika, mind/matter, empiris/rasional, deduktif/induktif, realis/nominalis, universal/particular, kolektif/individual, teleologis/ deontologis, objektif/subjektif, dan begitu seterusnya. Berpikir dikotomis seperti itu sebenarnya hanya merepresentasikan satu tingkat aras berpikir saja (one-rank thinking), karena hanya memperhatikan pada satu faktor saja. Padahal pada masing-masing pasangan diatas, dapat dilihat saling melengkapi (complementary). Contoh, agama dan ilmu dalam penglihatan awam bisa jadi terlihat kontradiksi, dan ada kecenderungan meletakkan agama atau wahyu ilahi sebagai lebih sentral 39 Jasser Auda, Ibid. Hlm. 48-49. 194 Landasan Epistemologi... atau lebih penting, akan tetapi jika dilihat dari dimensi lain, keduanya dapat saling melengkapi dalam upaya manusia untuk mencapai kebahagiaan atau jika dilhat dari upaya manusia untuk menjelaskan asal mula kehidupan, dan begitu seterusnya. Begitu juga mind dan matter dapat dilihat sebagai dua hal yang berlawanan dalam hubungannya dengan data-data sensual, tetapi keduanya dapat dilihat saling melengkapi jika dilihat dari sudut pandang teori-teori kognisi atau ilmu tentang kerja otak dan intelegensi buatan (artificial intelligence). Dari uraian ini, tampak bahwa cara berpikir manusia seringkali terjebak pada pilhanpilihan palsu yang bersifat biner, seperti pasti/tidak pasti, menang/ kalah, hitam/putih, tinggi/rendah, baik/buruk dan begitu seterusnya.40 Analisis Sistematik memperlihatkan bahwa pola pikir madhhab tradisional hukum Islam seringkali terjebak pada pola berpikir satu dimensi berpikir (one-dimensional) dan oposisi biner. Metode one-dimensional hanya terfokus pada satu faktor yang terdapat dalam satu kasus. Oleh karena itu, sebagian besar fatwa-fatwa yang dikeluarkan hanya berdasarkan satu dalil saja. Sering diistilahkan dengan dalil al-mas’alah (the evidence of case), meskipun sebenarnya selalu terbuka variasi dalil yang bermacammacam (adillah) yang dapat diterapkan pada kasus yang sama dan menghasilkan keputusan hukum yang berbeda. Hal yang sangat penting untuk dipahami dalam kaitan ini adalah bagaimana mendudukkan nass. Dalam pengetahuan ulama tradisional, sesuai dengan pemahaman yang terdapat dalam kitab klasik (kitab kuning), konsep dalil nass dibagi menjadi dua: Qat’i (sudah pasti) dan Zanni (belum pasti). Kemudian Nass Qat’i ini, oleh ulama tradisional dibagi menjadi tiga, yaitu Qat’iyyat al-Dilalah (arti kebahasaannya pasti), Qat’iyyat al-Tsubut (Keotentikan sejarahnya/ kesahihannya pasti) dan al-Qat’i al-Mantiqi (logikanya pasti).41 Sebenarnya konsep Qat’i ini yang merumuskan adalah ulama tradisional berdasarkan dugaaan mereka, yang kemudian dinyatakan sebagai ‘kebenaran pasti’. Menurut Jasser Auda, saat sekarang ini, untuk mengukur dan 40 41 Jasser Auda, Ibid. Hlm. 50 Jasser Auda, Ibid. Hlm. 214 Bab 4 195 memvalidasi “kebenaran” hendaknya diukur dengan ukuran apakah ditemukan bukti pendukung atau tidak? Semakin banyak bukti pendukung, maka semakin kuatlah tingkat ‘kebenaran pastinya’ (the principle of evidentalism). Sedang Khaled Abou al-Fadl memperkuat basis asumsi dasar untuk memvalidasi kesahihan pemikiran dan tindakan keagamaan di tengah perubahan sosial yang dahsyat di era globalisasi yaitu adanya asumsi dasar selain berbasis iman, tetapi juga berbasis nilai, metode dan juga berbasis akal.42 Menurutnya, kontradiksi yang sepertinya ada hanyalah ada pada segi bahasa, bukan pada segi logika yang selalu dikaitkan dengan waktu saat teks dirumuskan. Jika cara pandang ini dipakai, maka yang menjadi acuan adalah apakah ‘secara substansi’ terdapat pertentangan atau tidak dalam teks-teks tersebut? Oleh karenanya, sangat penting mempertimbangkan dan melibatkan aspek historis-sosiologis dan ekonomis dalam menyikapi permasalahan ta’arud al-adillah, dan lebih-lebih persoalan sosial-ekonomi dalam hubungannya dengan agama, yang jauh lebih kompleks. Menurut Jasser, untuk mengatasi problematika ini, para ulama fiqh kontemporer seharusnya menggunakan kerangka pikir Maqasid, yaitu mengambil skala prioritas pada teks dengan mempertimbangkan kondisi sosial yang ada dan tidak sekedar menganggap satu teks bertentangan dengan teks yang lain, kemudian dihapus, ditunda atau diberhentikan (mauquf). Sebab, bagaimana mungkin firman-firman Allah yang diturunkan oleh Allah sendiri saling bertentangan? Membenarkan permasalah ta’arud, justru akan merendahkan dan menuduh bahwa firman Allah tidak sempurna.43 Konsep naskh dan tarjih Khaled Abou el-Fadl. 2001. Speaking in God’s Name: Islamic Law, Authority, and Women, Oxford, Oneworld. 43 Jasser Auda, Ibid. Hlm. 216. Persoalan yang sama juga dihadapi oleh Abdullahi Ahmed an-Na’im ketika membahas problematika al-nasikh dan al-mansukh, antara ayatayat yang diturunkan di Madinah (Madaniyyah) dan ayat-ayat yang diturunkan di Makkah (Makkiyyah). Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa ayat-ayat yang turun belakangan (Madaniyyah) menghapus ayat-ayat yang turun duluan (Makkiyyah). An-Naim tidak sependapat dengan cara berpikir seperti itu. Dia memilih menggunakan istilah ‘menunda’, dan bukannya ‘menghapus’. Baik istilah ‘menunda’ dan lebih-lebih 42 196 Landasan Epistemologi... hanyalah menambah beban ketidak-fleksibelan atau kekakuan dalam hukum Islam. Refleksi mendalam tentang kedua pasang ayat atau periwayatan yang dianggap bertentangan menunjukkan bahwasanya ketidaksepakatan dalam pemahaman dapat saja disebabkan karena perbedaan di seputar lingkungan atau keadaan yang mengitari periwayatan tersebut, seperti situasi perang dan damai, kemiskinan dan kemakmuran, kehidupan desa dan kota, musim panas dan musim dingin, sakit dan sehat, tua dan muda dan seterusnya. Oleh karenanya, perintah atau anjuran al-Qur’an atau tindakan dan keputusan nabi, sebagaimana diceriterakan oleh para pengamat dan pemerhatinya, dapat diduga sangat mungkin dapat berbeda-beda antara yang satu dan lainnya.Ketidakmampuan para ahli hukum melakukan kontekstualisasi pasti akan berdampak langsung pada pembatasan fleksibilitas (lack of contextualisation limits flexibility). Sebagai contoh, menghapus atau tidak mempedulikan bukti-bukti yang biasa ada dalam konteks kehidupan yang damai, demi untuk mendahulukan atau memprioritaskan bukti-bukti yang ada dalam situasi perang, dibarengi dengan penggunaaan metode literal, secara otomatis akan membatasi kemampuan para ahli hukum untuk menanggapi kedua konteks tersebut secara proporsional. Jika cara berpikir ini digabungkan pula dengan metode berpikir yang memisahkan segala sesuatu secara biner secara ketat pula, maka hasil yang diperoleh adalah kesimpulan bahwa kebijakan dan aturan khusus yang sesungguhnya dimaksudkan hanya berlaku pada situasi dan kondisi tertentu saja akan dibuat menjadi universal dan berlaku selamanya.44 ‘menghapus’ memang sangat problematik bagi Jasser Auda. Lebih lanjut Abdullahi Ahmed an-Na’im. 1996. Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law, New York: Syracuse University Press. 44 Jasser Auda, Ibid. Hlm. 222. Uraian Jasser Auda ini mengingat kembali bagaimana Fazlur Rahman mengusulkan metode tafsir al-Qur’an dengan menggunakan pendekatan double movement (pendekatan bolak-balik) antara sisi Ideal-moral al-Qur’an - yang berdimensi universal - dan sisi legal-specific - yang dipraktikkan oleh umat Islam pada era atau periode waktu tertentu - supaya para pembaca nass-nass al-Qur’an tidak mudah terjatuh pada hanya satu sisi legal-specific, yang bersifat partial dan atomistik, dan kehilangan horison berpikir yang bermuatan ideal-moral, yang berlaku secara universal. Lebih lanjut Fazlur Bab 4 197 Jasser Auda mengajak para pembacanya untuk secara sungguhsungguh mulai mempertimbangkan dan menggunakan pendekatan kritis dan multi-dimensi terhadap teori hukum Islam di era kontemporer, agar supaya terhindar dari pandangan yang bercorak reduksionistik serta pemikiran klasifikatoris secara biner. Hanya dengan cara seperti itu, para pembaca dan pemerhati hukum Islam akan sadar bahwa hukum Islam sesungguhnya melibatkan banyak dimensi, antara lain sumber-sumber (sources), asal-usul kebahasaan (linguistic derivations), metode berpikir, aliran-aliran atau madhhab-madhhab berpikir, harus ditambah pula dimensi budaya dan sejarah, atau ruang dan waktu. Jika segmen-segmen tadi yang tidak terhubung dan ‘terdekonstruksi’, maka ia tidak akan dapat membentuk gambaran realitas hukum Islam yang utuh, kecuali jika kita mampu menjelaskannya kembali lewat skema keterhubungan yang sistemik dan keterhubungan secara struktural antar berbagai segmen tersebut. Jasser berkeyakinan bahwa pendekatan yang kritis, multi-dimensi, berpikir berbasiskan sistem serta berorientasi kepada tujuan akan mampu memberi jawaban kerangka beripikir yang memadai untuk keperluan analisis serta pengembangan teori hukum Islam, melebihi yang ditawarkan oleh kalangan postmodernis yang dilihatnya masih sedikit berbau oposisi biner, reduksionis dan uni-dimensional.45 6). Purposefulnes s/ Maqasid-based approach (Selalu mengacu kepada Tujuan) Tujuan). Kelima fitur yang dijelaskan di depan, yaitu kognisi (Cognitive nature), utuh (Wholeness, ), keterbukaan (Openness), hubungan hirarkis yang saling terkait (Interrelated Hierarchy), mulidimensi (Multidimensionality), dan diakhiri dengan Purposefulness sangatlah saling berkaitkelindan, saling berhubungan satu dan lainnya. Masing-masing fitur berhubungan erat dengan yang lain. Tidak ada satu fitur yang berdiri sendiri, terlepas Rahman, 1982. Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition, Chicago, The University of Chicago Press. Hlm. 5-7. 45 Jasser Auda, ibid. Hlm. 226-7. 198 Landasan Epistemologi... dari yang lain. Kalau saling terlepas, maka bukan pendekatan Systems namanya. Namun demikian, benang merah dan common linknya ada pada Purposefulness/Maqasid. Teori Maqasid menjadi projek kontemporer untuk mengembangkan dan mereformasi hukum Islam, termasuk upaya untuk mengonsep paradigma profetik dalam hukum Islam kontemporer. Teori Maqasid dan paradigm profetik kontemporer bertemu dengan standar basis metodologi yang penting, yaitu asas rasionalitas (Rationality), asas manfaat (Utility) asas keadilan (Justice) dan asas moralitas (Morality). Diharapkan upaya ini akan memberi kontribusi untuk pengembangan teori Usul alFiqh dan dapat pula menunjukkan beberapa kekurangannya (inadequacies)nya.46 Ada pertanyaan yang perlu diajukan. Mengapa prinsip Maqasid tidak begitu popular di lingkungan Usul al-Fiqh dan hukum Islam pada umumnya? Menurut Jasser Auda mungkin Usul al-Fiqh tradisional, sesuai dengan era perkembangan awalnya, masih dipengaruhi oleh pola pikir prinsip kausalitas ‘ala filsafat Yunani. Implikasi dari ekspresi atau istilah yang digunakan teks/nass tidak memasukkan a purpose implication (dilalah al-Maqsid). Ekspresi yang jelas (Imam Hanafi menyebutnya ‘ibarah; Imam Shafi’i menyebutnya sarih), yaitu jenis pembacaan langsung terhadap nass diberikan prioritas melebihi bentuk-bentuk ekspresi lainnya. Pembacaan seperti ini meniscayakan bentuk pemahaman yang literal (literal meaning) dalam bentuk muhkam, nass dan zahir. Sedangkan ekspresi maqsid (purpose), menurut mereka, hanya mungkin diperoleh pada salah satu dari kategori “non clear”, dengan menggunakan istilahistilah seperti iqtidha’. isyarah atau mufassar ataupun ilma’. Tipe-tipe term seperti ini, masih menurut mereka, kurang otoritasnya (lack of yuridical authority), karena bersifat uncertainty (zanniyyah).47 Kurangnya implication of purpose (Dilalah al-Maqasid) merupakan kekurangan yang sudah umum terjadi dalam kaitannya dengan legal text, bahkan dalam school of philosophy of law kontemporer sekalipun. 46 47 Jasser Auda, Ibid. Hlm. 228 Jasser Auda, Op.cit. Bab 4 199 The German School, khususnya Jhering dan French school, khususnya Geny menyerukan ‘purposefulness’ yang lebih besar di dalam hukum. Kedua kelompok ini menyerukan perlunya ‘reconstruction’ dalam hukum yang berbasis pada ‘interest’ dan ‘the purpose of justice’. Jhering menyerukan pergantian dari ‘mechanical law of causality’ ke ‘law of purpose’. Dia menegaskan sebagai berikut: Dalam ‘cause’ (sebab), objek yang menjadi akibatnya bersifat pasif. Sedangkan dalam ‘purpose’ (tujuan), sesuatu yang digerakkan bersifat self-active. Pada tataran perbuatan, cause mengacu pada masa lampau, sedangkan purpose mengacu pada masa depan. Dunia eksternal, ketika dipertanyakan alasan dari suatu proses, maka pertanyaan itu merujuk kembali ke belakang (masa lampau), selagi keinginan (will) mengarahkannya ke (masa) depan… Perbuatan dan perbuatan dengan tujuannya adalah sinonim (acting and acting with a purpose are synonymous). Perbuatan tanpa tujuan adalah sesuatu yang sama mustahilnya dengan akibat tanpa adanya sebab.48 Lebih jauh lagi, Geny menyerukan suatu metode yang memberikan signikansi yang lebih terhadap “tujuan perundang-undangan’ (legislative intent) yang diderivasi dari teks, kemudian memandu keputusan seorang penafsir (dictates the interpreter’s decision). Namun, seruan-seruan ini tidak terwujud menjadi sebuah perubahan besar dalam metodologi umum hukum positif saat ini. Jadi, peningkatan ‘purposefulness’ merupakan komponen yang dibutuhkan oleh filsafat hukum secara general. Sedangkan dalam sistem hukum Islam, the implication of the purpose (Dilalah al-maqsid) merupakan ekspresi baru yang akhir-akhir ini mengemuka di kalangan modernis Islam, dalam rangka memodernisasi Usul al-Fiqh. Selama ini, secara umum, dilalah al-maqsid memang belum dinilai sebagai dilalah qat’i (certain) untuk dijadikan sebagai suatu hujjah hukum (yuridical authority). Hingga sekarang, secara teoritis, purposefulness masih dilarang untuk memainkan peranan penting dalam upaya penggalian hukum dari nass. Berdasar landasan berpikir tersebut, Jasser Auda berkeyakinan bahwa tujuan dari hukum Islam (Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah) 48 Jasser Auda, Ibid. Hlm. 229. 200 Landasan Epistemologi... menjadi prinsip fundamental yang sangat pokok dan sekaligus menjadi metodologi dalam analisis yang berlandaskan pada Systems. Lagi pula, karena efektifitas dari sebuah sistem diukur berdasar pada terpenuhinya tujuan yang hendak dicapai, efektifitas dari sistem hukum Islam juga diukur berdasarkan terpenuhinya tujuan-tujuan pokoknya (Maqasid).49 Beberapa contoh pengambilan Maqasid dalam metode hukum Islam dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Istihsan (Yuridical Preference) berdasarkan Maqasid. Selama ini, Istihsan dipahami sebagai upaya untuk memperbaiki metode qiyas. Menurt Jasser Auda, sebenarnya permasalahannya bukan terletak pada ‘illat (sebab), melainkan pada Maqasidnya. Oleh sebab itu, Istihsan hanya dimaksudkan untuk mengabaikan implikasi qiyas dengan menerapkan maqasidnya secara langsung. Sebagai contoh: Abu Hanifah mengampuni (tidak menghukum) perampok, setelah ia terbukti berubah dan bertaubat berdasarkan Istihsan, meskipun ‘illat untuk menghukumnya ada. Alasan Abu hanifah, karena tujuan dari hukum adalah mencegah seorang dari kejahatan. Kalau sudah berhenti dari kejahatan mengapa harus dihukum? Contoh ini menunjukkan dengan jelas, bahwa pada dasarnya istihsan diterapkan dengan memahami dulu Maqasid dalam penalaran hukumnya. Bagi pihak yang tidak mau mengggunakan Istihsan, dapat mewujudkan Maqasid melalui metode lain yang menjadi pilihannya.50 2) Fath Dharai’ (Opening the Means) untuk mencapai Maqasid/tujuan yang lebih baik. Beberapa kalangan Maliki mengusulkan penerapan Fath Dharai’ di samping Sadd Dharai’. Al-Qarafi menyarankan, jika sesuatu yang mengarah ke tujuan yang dilarang harus diblokir (Sadd Dharai’) maka semestinya sesuatu yang mengarah ke tujuan yang baik harus dibuka (Fath Dharai’). Untuk menentukan peringkat prioritas harus didasarkan pada maqasid. Dengan demikian, dari kalangan Maliki ini, tidak membatasi diri pada sisi konsekwensi negatifnya saja, tetapi memperluas ke sisi pemikiran positif juga.51 3) ‘Urf (Customs) dan Tujuan Universalitas. Ibn Ashur menulis Maqasid Shari’ah. Dalam pembahasan tentang ‘Urf, ia menyebutnya sebagai ‘universalitas dalam Islam’. Dalam tulisan itu, ia tidak menerapkan ‘urf pada sisi riwayat, melainkan lebih pada Maqasidnya. Argumen Jasser Auda, Ibid. Hlm. 55. Jasser Auda, Ibid. Hlm. 239. 51 Jasser Auda, Ibid. Hlm. 241. 49 50 Bab 4 201 yang ia kemukakan sebagai berikut. Hukum Islam harus bersifat universal, sebab ada pernyataan bahwa hukum Islam dapat diterapkan untuk semua kalangan, di manapun dan kapanpun, sesuai dengan pesan yang terkandung dalam sejumlah ayat al-Qur’an dan hadis. Nabi memang berasal dari Arab, yang saat itu merupakan kawasan yang terisolasi dari dunia luar, yang kemudian berinteraksi secara terbuka dengan dunia luar. Agar tidak terjadi kontradiksi, maka sudah semestinya pemahaman tradisi lokal (baca: Arab) tidak dibawa ke kancah tradisi internasional. Jika demikian maka kemaslahatan tidak dapat dicapai dan tidak sesuai dengan Maqasid al-Syariah. Oleh sebab itu, kasus-kasus tertentu dari ‘urf tidak boleh dianggap sebagai peraturan universal. Cara berpikir ini cocok untuk mencari jalan keluar dari problem yang sedang dihadapi oleh minoritas Muslim di Barat dan Eropa khususnya. Ibn Ashur mengusulkan sebuah metode untuk menafsirkan teks/nass melalui pemahaman konteks budaya Arab saat itu. Demikian, Ibn Ashur membaca riwayat dari sisi tujuan yang lebih tinggi, dan tidak membacanya sebagai norma yang mutlak.52 4) Istishab (Preassumption of Continuity) berdasarkan Maqasid. Prinsip Istishab adalah bukti logis (dalilun ‘aqliyyun). Tetapi, penerapan prinsip ini harus sesuai dengan Maqasidnya. Misalnya, penerapan asas “praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah” (al-Aslu Bara’at alDhimmah), Maqasidnya adalah untuk mempertahankan tujuan Keadilan. Penerapan “Praduga kebolehan sesuatu sampai terbukti ada dilarang (al-aslu fi al-ashya’i al-ibahah hatta yadullu al-dalil ‘ala alibahah) Maqasidnya adalah untuk mempertahankan tujuan kemurahan hati dan kebebasan memilih.53 Akhirnya, dengan menggunakan pendekatan dan analisis Systems, Jasser Auda sampailah kepada usulan dan sekaligus kesimpulan yang mendasar dalam rangka merespon tantangan dan tuntutan era global sekarang , yaitu ketika umat Islam menjadi bagian dari penduduk dunia (world citizenship), dan bukannya hanya bagian dari penduduk lokal, yang khusus memikirkan dunia lokal-keummatannya sendiri. Masyarakat Muslim kontemporer dimanapun berada sekarang terikat dengan kesepakatan dan perjanjian-perjanjian internasional, khususnya setelah terbentuknya badan dunia seperti Persyarikatan Bangsa-Bangsa 52 53 Jasser Auda, Ibid. Hlm. 242. Jasser Auda, Ibid. Hlm. 243 202 Landasan Epistemologi... (PBB) dengan berbagai urusan sejak dari urusan kesehatan dunia (WHO), pangan-pertanian (FAO), pendidikan dan kebudayaan (UNESCO), perdagangan (WTO), keamanan (Dewan Keamanan PBB), perburuhan (ILO), perubahan iklim (climate change) dunia dan masih banyak yang lain.. Hukum-hukum yang berlaku di berbagai daerah lokal pun akhirnya bersinggungan dan berjumpa dan berdialog dengan hukum-hukum internasional. Salah satu isu kontemporer yang dihadapi umat Islam sekarang ini adalah tentang hak-hak asasi manusia (HAM). Sebagian umat Islam tidak dapat menerimanya sepenuh hati, karena masih terikat dengan konsep Maqasid Syari’ah yang lama, sedang sebagian besar yang lain menerimanya.54 Dalam upaya menjembatani gap antara hukum Islam yang lama dengan hukum Internasional yang disepakati oleh sebagian besar anggota PBB, maka Jasser Auda - setelah mendekomposisi teori hukum Islam Tradisional dengan memperbandingkannya dengan teori hukum Islam era Modern dan era Postmodern serta menggunakan kerangka analisis Systems yang rinci - mengusulkan perlunya pergeseran paradigma Teori Maqasid lama (Klasik) ke teori Maqasid yang baru. Pergeseran dari teori Maqasid lama yang disusun oleh al-Syatibi ke teori Maqasid baru, dengan mempertimbangkan perkembangan pemikiran warga dunia. Berikut adalah usulannya:55 Pergeseran Paradigma Teori Maqasid klasik menuju kontemporer No. Teori Maqasid klasik Teori Maqasid kontemporer 1. Menjaga Keturunan (al-Nasl) 2. Menjaga Akal (al-Aql) Teori yang berorientasi kepada perlindungan Keluarga; Kepedulian yang lebih terhadap institusi Keluarga. Melipatgandakan pola pikir dan research ilmiah; mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan; menekan pola pikir yang mendahulukan kriminalitas kerumunan gerombolan; menghindari upaya-upaya untuk meremehkan kerja otak. Pembahasan detil tentang hal ini dapat dijumpai dalam Abdullahi Ahmed an-Na’im, Ibid, Juga Mashood A. Baderin. 203. International Human Right and Islamic Law, Oxford New York: Oxford University Press. 55 Jasser Auda. Op. Cit. Hlm. 21-3. 54 Bab 4 203 No. Teori Maqasid klasik Teori Maqasid kontemporer 3. Menjaga kehormatan; menjaga jiwa (al-‘Irdh) Menjaga agama (alDiin) Menjaga harta (alMaal) Menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan; menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia. Menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan berkepercayaan. Mengutamakan kepedulian sosial; menaruh perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi; mendorong kesejahteraan manusia; menghilangkan jurang antara miskin dan kaya. 4. 5. Perubahan paradigma dan teori Maqasid yang lama ke teori Maqasid yang baru terletak pada titik tekan keduanya. Tiitk tekan Maqasid lama lebih pada protection (perlindungan) dan preservation (penjagaan; pelestarian) sedang teori Maqasid baru lebih menekankan pada development (pembangunan; pengembangan) dan right (hak-hak). Dalam upaya pengembangan konsep Maqasid pada era baru ini, Jasser Auda mengajukan ‘human development’ sebagai ekspresi obsesinya dan target utama dari maslahah (public interest) masa kini; maslalah inilah yang mestinya menjadi sasaran dari Maqasid al-Syari’ah untuk direalisasikan melalui hukum Islam. Selanjutnya, realisasi dari Maqasid baru ini dapat dilihat secara empirik perkembangannya, diuji, dikontrol, dan divalidasi melalui human development index dan human development targets yang dicanangkan dan dirancang oleh badan dunia, seperti Persyarikatan Bangsa-Bangsa dunia (PBB). Tidak hanya itu. Ketika tulisan ini seolah-olah hanya difokuskan pada bangunan tata pikir hukum Islam yang terkait dengan isu kepastian hukum dan keadilan, namun sesungguhnya radius jangkauan multiplyer efeknya jauh lebih luas dari itu. Berkembang tidaknya bangunan tata pikir epistemologi hukum Islam ini akan berpengaruh kuat pada bangunan pola pikir dan paradigma pendidikan agama (Islam) di sekolah-sekolah,56 pesantren, ma’had ali dan perguruan tinggi, tata dan pola komunikasi Untuk mempertajam implikasi dalam dunia pendidikan agama, dapat di telaah permasalahan pendidikan agama di tanah air dalam Th. Sumartana, dkk. 2005. Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan kedua. 56 204 Landasan Epistemologi... sosial umat beragama di ruang publik oleh para tokoh dan pimpinan organisasi agama,kekerasan sosial yang mengatasnamakan agama di ruang publik57 maupun kekerasan agama di ruang privat (domestic violence), sensitifitas dan asertifitas gender, tata dan pola pergaulan sosial dan politik di kancah multikulturalitas seperti Indonesia dan dunia pada umumnya, kepekaaan kepada budaya dan agama lokal yang nonAbrahamik, lebih-lebih hubungan antara Muslim dan non-Muslim di berbagai tempat di dunia.58 5. Keutamaan Etika/the Primacy of Ethics. Pendekatan Systems yang mencoba mengurai dan menganalisis sisi kognitif dari pemahaman usul al-fikih dan hukum Islam, sejak dari era Tradisional, Modern dan Postmodern tidak dimaksudkan hanya berhenti pada sisi kognitif-teoritis dan tidak berimplikasi pada sisi etika praksis dalam kehidupan beragama sehari-hari. Pendekatan Systems mempunyai implikasi praktis pada wilayah etika. Hukum tanpa etika bagaikan jasad tanpa ruh. Begitu pula sebaliknya, etika tanpa hukum bagaikan ruh tanpa jasad. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Begitu juga hubungan antara apa yang biasa disebut “kepastian hukum” dan “rasa keadilan”. Kepastian hukum tanpa rasa keadilan juga ibarat jasad tanpa ruh, begitu juga sebaliknya. Kepastian hukum (agama), yang umumnya dipandu oleh teks-teks keagamaan, menentukan “kepastian” hukum yang akan diambil oleh para hakim agama di tingkat lapangan. Cara berpikir hakim pada umumnya adalah demikian adanya, baik pada tataran hukum positif maupun hukum agama. Kepastian hukum umumnya dipahami sebagai hukum yang ditetapkan sesuai dengan bunyi teks yang ada di Dapat dicermati Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2009. Program Studi Agama dan Lintas Budaya (Center for Religious & Cross-Cultural Studies /CRCS), Sekolah Pascasarjana, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2009, Hlm. 27-52. 58 Waleed El-Ansary dan David K. Linnan (Ed.). 2010. Muslim and Christian Understanding: Theory and Application of “A Common Word”, New York: Palgrave Macmillan. Untuk konteks Indonesia, dapat ditelusuri sejarah perkembangan dialog antar umat beragama di Indonesia, J.B. Banawiratma, Zainal Abidin Bagir, etc. 2010. Dialog Antarumat Beragama: Gagasan dan Praktik di Indonesia, Jakarta: Mizan Publika. 57 Bab 4 205 tangan para hakim. Pengambilan keputusan hukum yang dianggap pasti (kepastian hukum) segera akan menjadi bahan perbincangan umum tentang adanya aroma ketidakadilan jika tidak dibarengi pertimbanganpertimbangan etis-humanistik, betapapun kuatnya sandaran pada teksteks aturan hukum yang tersedia. Sekedar sebagai contoh, apakah seseorang yang memeluk agama non-Islam di suatu keluarga Muslim akan memperoleh warisan atau tidak, jika orang tua meninggal? Jika hakim di peradilan agama di tingkat lokal berargumen bahwa seorang anak yang menganut agama non-Islam tidak akan mendapatkan warisan karena teks-teks positifkeagamaan yang dianutnya melarangnya, maka keputusan demikian secara etis kemanusiaan - akan menimbulkan masalah kemanusiaan. Dalam negara-negara yang tidak bercorak teokratis, seperti Indonesia, maka hal tersebut akan menimbulkan atau setidaknya menyisakan masalah keadilan (wilayah etika). Meskipun secara positif dan tegas, teks-teks hukum agama Islam tidak membolehkan memberikan warisan kepada anak keturunan yang menganut agama non-Islam (kepastian hukum), namun secara sosiologis dan humanities, kepastian hukum seperti itu akan menyentuh rasa ketidakadilan. Keputusan hakim di tingkat lokal dapat dibatalkan oleh putusan mahkamah yang berada diatasnya, pada tingkat banding atau kasasi. Demi keadilan dan pertimbangan kemanusiaan (pertimbangan etis), mahkamah di tingkat naik banding dan kasasi dapat membatalkan keputusan hakim di tingkat bawah. Bagaimana manghindari putusan-putusan hakim agama yang tidak sejalan dengan rasa keadilan? Tidak hanya pada persoalan warisan, tetapi ada pada persoalan lain seperti hak-hak reproduksi wanita, hakhak asasi manusia dan begitu seterusnya. Untuk mengukur apakah keputusan hakim itu adil, kurang atau tidak adil, barometernya tidak pada teks keagamaan atau hukum-hukum positif yang tertuang dalam undang-undang atau peraturan dan sejenisnya, melainkan terletak para pribadi para hakim itu sendiri. Oleh karenanya, wawasan keilmuan, pandangan atau world view keagamaan 206 Landasan Epistemologi... dan horizon berpikir para hakim umum dan agama – kembali lagi menggarisbawahi sisi kognisi yang dimiliki para hakim dan agamawan sangat penting disini - sangat menentukan kualitas keadilan yang dituntut oleh para pencari keadilan di depan hukum. Para hakim memerlukan knowledge dan skill yang lebih dari cukup agar supaya dapat melakukan fresh ijtihad terhadap berbagai persoalan hukum baru yang dihadapi sehari-hari dalam konteks yang berbeda-beda dari satu wilayah ke wilayah yang lain, dari satu provinsi ke pronvinsi yang lain, dari budaya yang satu ke budaya yang lain, bahkan dari negara ke negara yang lain. Khaled Abooe el-Fadl secara tegas berpendapat bahwa dalam era perubahan sosial yang dahsyat seperti saat sekarang ini, knowledge dan skill para hakim, bahkan para penganut agama-agama dunia, perlu terus menerus diperbaharui dan di update. Selain berlandaskan imanagama, seseorang, kelompok dan apalagi para hakim agama sangat perlu di tambah dengan bekal pengetahuan tentang nilai (value), metode (methods) dan rasionalitas (rationality). Untuk mempertahankan dan mendahulukan etika kemanusiaan universal, agama saja - dalam hal ini adalah iman - adalah tidak cukup. Untuk membuat seseorang beragama berperilaku etis, diperlukan syarat lain yang perlu dipenuhi yaitu pemahaman tentang nilai, metode dan rasionalitas. Perilaku etis, menurutnya, juga harus terukur. Setidaknya ada lima syarat yang diajukan, yaitu: 1) Honesty (kejujuran). Manusia beragama harus jujur dengan diri sendiri, bahwasanya manusia penuh dengan keterbatasan-keterbatasan, betapapun kuatnya kekuasaan atau ilmu yang dimilikinya. Manusia beragama juga memiliki keterbatasan-keterbatasan yang inherent dalam diri dan kelompoknya. 2) Diligence (sungguh-sungguh, serius, itqan). Tidak dengan mudah menyepelekan atau menganggap ringan sebuah persoalan atau masalah. Harus dengan tekun dan serius menyelesaikan masalah dan mencari tahu tentang persoalan yang sedang dihadapi. Al-Qur’an secara tegas mencela orang-orang beragama yang berani-berani mengklaim tahu tentang Tuhan atau Bab 4 207 atas nama Tuhan tanpa basis ilmu pengetahuan yang kuat, tapi hanya sekedar atas dasar keinginan kosong, kesombongan atau kepentingan pribadi/kelompok. Bandingkan dengan surat alBaqarah, 80; 169; al-A’raf, 28; 33 dan Yunus, 69-9. 3) Comprehensivess (menyeluruh-utuh). Memahami petunjuk teks kitab suci al-Qur’an secara utuh, tidak parsial-fragmentaris dan tidak pula secara selektif berdasarkan tarikan kepentingan-kepentingan atau nafsu diri pribadi, apalagi golongan, madzhab atau aliran. 4) Reasonableness (masuk akal). Banyak ukuran kemasukakalan dalam melakukan interpretasi terhadap teks dan melakukan tindakan keagamaan, antara lain adalah adanya komunitas interpretasi yang dapat memberi pertimbangan dapat diterima atau tidaknya sebuah idea atau perintah sosial-keagamaan. Lebih-lebih persoalan sosialkeagamaan Islam di lingkungan minoritas Muslim di negara-negara Barat. 5) Self-restraint (Kemampuan menahan diri). Agamawan yang baik, sederhana dan rendah hati selalu dapat menahan diri. Menghindari tindakan memaksakan kehendak terhadap orang lain dengan kekuatan atau kekerasan. Ungkapan yang biasa dikutip para penulis Muslim “wa Allahu a’lam bi sawab” (dan Allah lah yang Maha Mengetahui yang benar), sejatinya menunjukkan adanya moral dan epistemological disclaimer dari seorang Muslim. Manusia Muslim diminta menolak untuk mudah-mudah mengklaim kebenaran moral dan epistemologis atas namanya sendiri atau golongannya.59 6. Penutup Upaya untuk mengkonstruksi dan membangun kembali paradigma profetik dalam hukum dan hukum Islam era kontemporer adalah sejalan, seiring dan sehaluan dengan keinginan para akademisi Muslim di perguruan tinggi dunia yang concern untuk mendialogkan dan memperjumpakan secara sungguh-sungguh rancang bangun epistemologi dan pola pikir usul fikih dan hukum Islam yang bercorak tradisional dengan paradigma usul fikih dan hukum Islam yang lebih sensitif terhadap problem pemikiran keagamaan dunia dan perkembangan pola pikir usul fikih dan hukum Islam pada era 59 Khaled Abou El-Fadl, Op. Cit. Hlm. 54-6. 208 Landasan Epistemologi... modernitas dan postmodernitas yang secara serius melibatkan disiplin ilmu lain seperti metode berpikir sains, ilmu sosial dan humanities kontemporer. Ketika disebut profetik, imajinasi intelektual dan kesejarahan para pembaca janganlah cepat-cepat mengaitkannya dengan ajakan untuk kembali ke era kenabian Muhammad dengan melupakan sejarah panjang perkembangan pola pikir umat Islam di seantero dunia dan lebih-lebih lagi bukan pula secara serta merta melupakan sejarah panjang pembentukan pola pikir hukum umat Islam dan konteks kesejarahan kitab-kitab kuning (kitab-kitab keagamaan era klasik dan atau medieval) yang terlanjur dianggap mu’tabarah oleh kelompok tertentu tetapi tidak dianggap demikian oleh kelompok yang lain. Belum lagi, harus pula mempertimbangkan sejarah pemikiran keagamaan dan pemikiran hukum yang terjadi pada bangsa-bangsa lain di dunia. Aspek kesejarahan yang meliputi Tradisionalitas, Modernitas dan Postmodernitas dengan berbagai implikasi dan konsekwensinya perlu dipahami dan dicermati terlebih dahulu oleh para peminat studi hukum. Di samping aspek kesejarahan, kerangka berpikir, epistemologi dan logika keilmuan dan kefilsafatan yang menyertainya juga samasama pentingnya untuk dicermati. Dalam setiap etape sejarah yang dilalui, secara implisit maupun eksplisit mengandung fondasi logika berpikir yang menyertainya. Pendekatan Systems yang diuraikan di depan dapat membantu menguak dan merekonstruk paradigma berpikir dalam setiap etape sejarah yang dilalui. Kaca mata pendekatan Systems dengan ke 6 (enam) fiturnya diatas diharapkan dapat membantu para peminat studi hukum membangun kerangka pikir usul fikih dan hukum Islam yang baru, yang lebih sensitif terhadap perbedaan dan titik temu antar ketiga era sejarah yang dilalui umat Islam dan mendialogkannya secara cermat dengan selalu melihat dan mencermati implikasi dan konsekwensinya masing-masing dalam memperbincangkan “keadilan” dan “kepastian hukum”. Dengan pangkal tolak berpikir keagamaan bahwa profetik adalah pro(f)etik, maka keutamaan etik - yang lebih Bab 4 209 bercorak humanistik, dan bukan mengejar target kepastian hukum yang bercorak positivistik - diharapkan dapat membantu upaya menghidupkan kembali semangat fresh ijtihad terhadap teori dan praktik hukum secara umum dan hukum Islam secara khusus - baik di tingkat lokal maupun global - dalam kerangka besar diskusi ilmu hukum kontemporer. Wa Allahu a’lam bi al sawab. E. Basis Epistemologi Ilmu Hukum Profetik Oleh M. Syamsudin Menurut Kuntowijoyo, basis utama epistemologi Ilmu (Sosial) Profetik adalah Ajaran Islam. Untuk memahami bangunan ajaran Islam tersebut Kuntowijoyo menggunakan pendekatan strukturalisme transendental. Pendekatan strukturalisme sendiri diintrodusir dari pendapat Michael Lane dalalm buku Introduction to Structuralism (New York: Basi Books Inc, 1970) yang mempunyai ciri-ciri: keseluruhan (wholeness), perubahan bentuk (transformation), dan mengatur diri sendiri (self-regulation).60 Menurut Kuntowijoyo, strukturalisme memperhatikan pada keseluruhan atau totalitas (wholeness). Strukturalisme mengkaji unsur tetapi unsur itu selalu diletakkan di bawah suatu jaringan yang menyatukan unsur-unsur tersebut. Jadi unsur hanya dapat dimengerti melalui keterkaian antar unsur lainnya (interconnectedness). Strukturalisme tidak mencari struktur di permukaan, pada peringkat pengamatan, tetapi di bawah atau di balik realitas empirik. Apa yang ada di permukaan adalah cerminan dari struktur yang ada di bawah (deep structure) dan lebih ke bawah lagi ada kekuatan pembentuk struktur (innate structuring capacity). Dalam peringkat empiris keterkaitan antar unsur dapat berupa binary opposition (pertentangan antara dua hal). Strukturalisme memperhatikan Kuntowijoyo. 2006. Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika. Yogyakarta: Tiara Wacana. Hlm.29. 60 Landasan Epistemologi... 210 unsur-unsur yang sinkronis, bukan yang diakronis. Berikut ini adalah skema struktur transendental ajaran Islam.61 Skema Strukturalisme Transendental (Kuntowijoyo, 2006) Tauhid Akidah Ibadah Keyakinan Sholat/ Puasa/ Zakat/ Haji Kekuatan Pembentuk Akhlak Syariat Muamalah Moral/ Etika Perilaku Normatif Perilaku sehati-hari Struktur Dalam Struktur Permukaan Dari bagan tersebut dijelaskan oleh Ahimsa-Putra, bahwa dalam Islam, keterkaitan (interconnectedness) adalah sangat ditekankan. Misalnya keterkaitan antara puasa dan zakat, hubungan vertikal (dengan Tuhan) dengan hubungan horizontal (antar manusia), dan antara sholat dengan solidaritas sosial. Keterkaitan itu kadang-kadang secara eksplisit disebutkan di dalam ajaran, seperti antara sholat dengan solidaritas sosial. Misal dalam QS.Al-Ma’un disebutkan, bahwa termasuk orang yang mendustakan agama bagi mereka yang sholat tapi tidak mempunyai kepedulian sosial terhadap kemiskinan. Demikian pula keterkaitan antara iman dan amal sholeh. Dengan demikian epistemologi Islam adalah epistemologi relasional, satu unsur selalu ada hubungannya dengan lainnya. Keterkaitan itu dapat sebagai logical consequences dari satu unsur. Seluruh rukun Islam lainnya (sholat, zakat, puasa, haji) adalah konsekuensi logis dari syahadah. Zakat adalah konsekuensi logis dari puasa, yaitu setelah orang merasakan sendiri penderitaan, lapar dan haus.62 61 62 Ibid. Hlm.33. Heddy Shri Ahimsa-Putra, Op.Cit. Bab 4 211 Dalam Islam innate structuring capacity ditunjukkan oleh tauhid. Tauhid mempunyi kekuatan membentuk struktur yang paling dalam. Sesudah itu ada deep structure yaitu akidah, ibadah, akhlak, syariah dan muamalah. Di permukaan yang dapat diamati berturut-turut akan tampak keyakinan, sholat/puasa dst, moral/etika, perilaku normatif dan perilaku sehari-hari. Akidah, ibadah, ahklak dan syariat itu immutable (tidak berubah) dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat sedangkan muamalah itu dapat saja berubah. Transformatio dalam islam yang sudah utuh, harus diartikan sebagai transformasi dalam muamalah dan tidak dalam bidang lain. Binnary opposition dalam islam ditujukkan oleh dua gejala yang saling bertentangan yaitu pasangan (azwaj) dan musuh (’aduwun) yang masing-masing menghasilkan ekuilibrium dan konflik. Dalam strukturalisme, pertentangan yang berupa pasanganlah yang dimaksud. Pertentangan antara kepentingan manusia dengan kepentingan Tuhan, badan dengan ruh, lahir dan bati, dunia dan akhirat, laki-laki dan perempuan, muzaki dan mustahiq, orang kaya dan orang miskin, dan lain-lain pasangan yang menghasilkan ekuilibrium. Sementara itu ada pertentangan antar struktur yang menghasilkan konflik, karena orang harus memilih salah satu. Pertentangan antara Tuhan dengan setan, dzulumat dengan nur, syukur lawan kufur, saleh lawan fasad, surga lawan neraka, muthmainnah lawan amarah, halal lawan haram, dsb jenis pertentangan yang menghasilkan konflik.63 Menurut Ahimsa-Putra, oleh karena Islam dapat dimaknai berbagai macam, maka perlu ada rumusan minimal tentang apa yang dimaksud dengan Islam di sini. Menurut Ahimsa-Putra, Islam di sini dapat dimaknai sebagai keseluruhan perangkat simbol yang berbasis pada simbol-simbol yang bersumber pada kitab Al Qur’an dan Sunnah Rasul sebagai utusan Allah s.w.t. yang menjelaskan dan mewujudkan berbagai hal -jika bukan semua hal yang ada- dalam Al Qur’an. 63 Kuntowijoyo, Op.Cit. hlm. 32-34. 212 Landasan Epistemologi... Lebih lanjut dikemukakan bahwa, ajaran Islam itu bersumber dari Al Qur’an dan Sunnah Rasul, dengan demikian dalam konteks IlmuIlmu Profetik segala sesuatu yang ada dalam Al Quran dan Sunnah Rasul harus diketahui dan dipahami dengan baik terlebih dulu, untuk dapat dijadikan landasan bagi keseluruhan bangunan Ilmu-Ilmu Profetik. Tentu saja tidak semua unsur dalam Al Quran dan Sunnah Rasul relevan dengan pengembangan Ilm-Ilmu Profetik. Untuk itu, pengetahuan dan pemahaman tentang unsur-unsur yang relevan akan sangat membantu dalam pengembangan ilmu tersebut. Di sini diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang baik dan benar mengenai Al Quran dan Sunnah Rasul serta pengetahuan dan pemahaman mengenai Filsafat Ilmu pada umumnya. Untuk memudahkan memahami Al Qur’an dan Sunnah Rasulullah s.a.w. sebagai basis utama Ilmu-Ilmu Profetik dibutuhkan sebuah model yang dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi asumsi-asumsi dasar. AhimsaPutra menawarkan Rukun Iman dan Rukun Islam sebagai sebuah model dalam bangunan paradigma Ilmu-Ilmu Profetik. Rukun Iman merupakan basis keyakinan, basis kepercayaan, basis yang terdiri dari dua macam yaitu: basis kognisi (pikiran) dan basis afeksi (perasaan). Rukun Iman adalah hal-hal yang harus diyakini oleh seorang Muslim, yang terdiri dari enam hal, yakni iman kepada: (1) Allah, (2) malaikat, (3) Kitab-kitab, (4) Rasul-rasul (para Nabi), (5) Hari Kiamat, Hari Pengadilan dan (6) Takdir (Qadha dan Qadar). Rukun Iman ini berada pada bidang keyakinan tentang pandangan-pandangan tertentu dalam agama. Agar relevan dengan Ilmu Profetik, maka Rukun Iman ini perlu ditransformasikan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan konteksnya, yakni konteks keilmuan. Pertanyaannya adalah bagaimana mentransformasikan keenam rukun iman tersebut? Jika direnungkan lebih lanjut, ’iman’ tersebut tidak lain adalah ’relasi’. Beriman kepada Allah berarti ’membangun relasi dengan Allah’, dan relasi yang paling tepat adalah ’pengabdian’. Dalam konteks Ilmu Profetik, Allah di sini ditransformasikan menjadi Pengetahuan, Bab 4 213 karena Allah adalah Sumber Pengetahuan. Beriman kepada Allah dalam konteks Ilmu Profetik adalah mengimani pengetahuan itu sendiri yang bersumber pada Allah. Beriman kepada malaikat berarti ’membangun relasi dengan malaikat’, dan relasi yang tepat adalah ’persahabatan’, karena malaikat adalah sahabat atau teman orang yang beriman. Beriman kepada Kitab adalah membangun relasi dengan kitab, dan relasi yang tepat adalah ’pembacaan’, karena kitab adalah sesuatu yang dibaca. Beriman kepada Nabi adalah membangun relasi dengan Nabi, dan relasi yang tepat adalah ’perguruan dan persahabatan’. Artinya, seorang Muslim memandang Nabi sebagai guru yang memberikan pengetahuan, sekaligus juga sahabat, sebagaimana hubungan yang terjadi antara Nabi Muhammad s.a.w. dengan para sahabatnya. Beriman kepada Hari Kiamat adalah membangun relasi dengan hari Kiamat, dan relasi yang tepat adalah ’pencegahannya’, karena Kiamat dalam konteks ini dapat ditafsirkan sebagai ’kehancuran’. Beriman kepada Takdir adalah membangun relasi dengan Takdir, dan relasi yang tepat adalah “penerimaannya”. Artinya seorang muslim memandang takdir sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindarkan, dan karena itu relasi yang tepat adalah menerimanya. Takdir dalam konteks keilmuan dapat ditafsirkan sebagai “hukum alam”. Rukun Islam ada lima, yaitu: (a) membaca kalimat syahadat; (b) mendirikan sholat; (c) menjalankan puasa; (d) mengeluarkan zakat; dan (e) naik haji. Sebagaimana Rukun Iman, dalam konteks Ilmu-Ilmu Profetik, Rukun Islam tentunya juga perlu ditransformasikan ke dalam praktik kehidupan ilmiah sehari-hari. Rukun Islam harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sinilah Rukun Islam akan menjadi wujud dari etos yang ada dalam Ilmu-Ilmu Profetik, dan basis dari praktik kehidupan ilmiah ini adalah transformasi Rukun Iman yang pertama, yaitu pengabdian, karena pada dasarnya Rukun Islam adalah perwujudan dalam bentuk tindakan atau praktik, dari keimanan. Menurut Ahimsa-Putra, basis utama Alquran dan Sunnah Rasul yang berupa Rukun Iman dan Rukun Islam diturunkan lagi menjadi Landasan Epistemologi... 214 asumsi-asumsi dasar mengenai: (a) basis pengetahuan; (b) objek material; (c) gejala yang diteliti; (d) ilmu pengetahuan; (e) ilmu sosialbudaya/alam; (f) disiplin. Berkenaan dengan Ilmu-Ilmu Profetik, isi dari asumsi-asumsi dasar ini sebagian sama dengan ilmu-ilmu di barat pada umumnya, sebagian yang lain berbeda. Berikut ini digambarkan skema tentang basis epistemologis Ilmu-Ilmu Profetik. Skema tentang Basis Epistemologis Ilmu-Ilmu Profetik (Sumber: Ahimsa-Putra, 2011) Asumsi dasar tentang Gejala Yang Diteliti indera kemampuan strukturasi dan simbolisasi bahasa wahyu - ilham sunnah Rasulullah saw. asal - mula sebab - sebab hakekat asal - mula sebab - sebab hakekat Asumsi dasar tentang Ilmu Pengetahuan tujuan hakekat macam Asumsi dasar tentang Basis Pengetahuan Rukun Iman Basis Epistemologis Al Quran dan Sunnah Rasul Rukun Islam Asumsi dasar tentang Obyek Material Asumsi dasar tentang Ilmu Sosial/Budaya Alam/Profetik Asumsi dasar tentang Disiplin Profetik tujuan hakekat macam tujuan hakekat macam Untuk keperluan analisis terkait dengan bangunan Ilmu Hukum Profetik, unsur-unsur dari asumsi-asumsi dasar yang terdapat pada skema tersebut akan dicoba diberikan uraian meskipun tidak secara keseluruhan karena masih sangat terbatasnya informasi di sini. Ada tiga hal yang akan diuraikan yaitu asumsi dasar tentang basis pengetahuan, asumsi dasar tentang objek materiil dan asumsi dasar tentang disipilin. Tiga hal ini sementara dijadikan dasar bangunan dari Ilmu Hukum Profetik. Bab 4 215 1. Asumsi Dasar tentang Basis Pengetahuan Menurut Ahimsa-Putra, asumsi dasar di sini dimaksudkan sebagai pandangan mengenai hakikat dari ilmu itu sendiri. Dalam Filsafat Ilmu di Barat, dikenal adanya dua pandangan yang berlawanan mengenai ilmu yang masih terus diusahakan pendamaiannya. Pandangan pertama mengatakan bahwa ilmu itu adalah satu, sehingga tidak ada yang namanya ilmu alam dan ilmu sosial-budaya. Menurut pendapat ini meskipun ada perbedaan pada objek material antara ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial-budaya, namun ilmu tidak perlu dibagi menjadi dua hanya karena objek materialnya berbeda.64 Pandangan kedua mengatakan bahwa ilmu ada dua macam, yaitu ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial-budaya, karena objek material masing-masing memang berbeda. Menurut pendapat ini, hakikat gejala sosial-budaya yang diteliti oleh ilmu-ilmu sosial-budaya berbeda dengan hakikat gejala-gejala yang dipelajari dalam ilmu alam. Oleh karena itu, ilmu-ilmu sosial-budaya tidak sama dengan ilmu-ilmu alam, karena dalam ilmu-ilmu sosial-budaya diperlukan metode-metode tertentu untuk mempelajari dan memahami gejala sosial-budaya yang berbeda dengan gejala alam.65 Ilmu-ilmu Profetik dengan sendirinya memiliki pandangan yang berbeda juga dengan pandangan-pandangan di atas. Pencanangan IlmuIlmu Profetik sebagai ilmu yang berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain menunjukkan adanya asumsi bahwa ilmu profetik berbeda dengan ilmuilmu yang telah ada, yakni ilmu alam dan ilmu sosial-budaya. Elemen wahyu inilah yang membedakan ilmu-ilmu profetik dengan ilmu-ilmu yang lain. Mengenai hal ini diperlukan paparan yang lebih mendalam, yang belum dilakukan di sini.66 Hedi Sri Ahimsa-Putra, “Paradigma Profetik sebuah Konsepsi”, Makalah disampaikan dalam Diskusi Pengembangan Ilmu Profetik 2011,diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum - UII, di Yogyakarta, 18 Nopember 2011. 65 Ibid. 66 Ibid 64 216 Landasan Epistemologi... Dalam konteks Ilmu Hukum, selain memiliki persamaanpersamaan, Ilmu Hukum Profetik juga memiliki perbedaan-perbedaan pada asumsinya, sehingga ada perbedaan antara Ilmu Hukum Profetik dengan Ilmu Hukum pada umumnya (yang tidak profetik). Asumsiasumsi ini sebagian besar berasal dari Ilmu Hukum pada umumnya, sebagian lagi tidak. Berdasarkan pemahaman ini dapat diasumsikan untuk sementara bahwa Ilmu Hukum Profetik adalah Ilmu hukum yang mempelajari gejala-gejala hukum baik yang bersumber dari wahyu maupun dari manusia. Dari asumsi dasar ini lebih lanjut dijabarkan asumsi-asumsi dasar terkait dengan basis pengetahuan, disiplin, dan objek material Ilmu Hukum Profetik. Ilmu-Ilmu Profetik memiliki asumsi-asumsi dasar tentang basis dari pengetahuan manusia. Asumsi-asumsi ini ada yang sama dengan asumsi-asumsi yang ada dalam ilmu pada umumnya, ada pula yang tidak, sebab kalau basis pengetahuan ini semuanya sama, maka tidak akan ada bedanya antara Ilmu-Ilmu Profetik dengan ilmu-ilmu pada umumnya. Berikut adalah basis yang memungkinkan manusia memiliki pengetahuan, dan dengan pengetahuan tersebut manusia dapat melakukan transformasi-transformasi dalam kehidupannya, yakni: a. Indera b. Kemampuan Strukturasi dan Simbolisasi (Akal) c. Bahasa (Pengetahuan Kolektif) d. Wahyu e. Sunnah Rasul Kuntowijoyo tidak menyinggung tentang Sunnah Rasul sebagai salah satu sumber pengetahuan. Ahimsa-Putra memasukkannya, karena dalam agama Islam, Al Qur’an tidak pernah dapat dipisahkan dari sunnah Rasulullah s.a.w. Ketika manusia di masa Rasulullah s.a.w. tidak dapat memahami dengan baik makna ayat-ayat yang turun, makna wahyu yang turun, mereka bertanya kepada Rasulullah s.a.w., karena melalui beliaulah wahyu tersebut turun. Pemahaman kita, tafsir kita mengenai berbagai ayat dalam Al Qur’an selalu awalnya bersumber Bab 4 217 dari penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Rasulullah s.a.w. atau perilaku dan tindakan beliau yang berdasarkan wahyu-wahyu tersebut. Dalam Islam, Al Qur’an dan Sunnah Rasul adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena Rasulullah s.a.w. adalah “Al Qur’an yang berjalan”, Al Qur’an yang mewujud dalam bentuk ucapan, perilaku dan tindakan. Jika kita menempatkan wahyu sebagai salah satu sumber pengetahuan, maka penjelasan tentang wahyu tersebut oleh penerima wahyu itu sendiri tentu tidak dapat diabaikan. Bagi Ilmu Hukum Profetik, wahyu (yang sumbernya Alquran) dan Sunah Rasul justru menjadi sumber utama pengetahuan manusia untuk menetapkan hukum. Sumber-sumber lain seperti bahasa, akal dan indera menjadi sumber pendukungnya. Yang perlu menjadi catatan di sini sumber pengetahuan manusia yang berasal dari wahyu dan hadits rasul tersebut masih perlu ditransformasi dalam bentuk norma atau kaidah atau putusan hukum yang sesuai dengan konteks sosio-kultural masyarakatnya. Artinya sumber-sumber tersebut harus diolah secara matang bersama sumbersumber pengetahuan pendukung yaitu bahasa, akal dan indera agar mudah dipahami dan dipraktikkan. Ini membutuhkan strategi dan teori tertentu yang dapat menjembatani masalah tersebut. 2. Asumsi Dasar tentang Objek Material Jika kritik yang dilontarkan terhadap ilmu pada umumnya adalah sifatnya yang sekuler, maka kelemahan inilah yang tidak boleh terulang dalam Ilmu Hukum Profetik. Artinya, di sini harus dilakukan desekularisasi, yang berarti memasukkan kembali unsur sakral, unsur ke-Ilahi-an dalam ilmu (hukum) profetik. Bagaimana caranya? Menurut Ahimsa-Putra, salah satu caranya adalah dengan menempatkan kembali segala objek material Ilmu Profetik dan Ilmuwan Profetik dalam hubungan dengan Sang Maha Pencipta, Allah s.w.t. atau Tuhan Yang Maha Kuasa (dimensi transendensi). Di sini perlu diasumsikan bahwa meskipun alam dan kehidupan manusia adalah sebuah realitas yang ada, namun realitas ini tidak muncul dengan 218 Landasan Epistemologi... sendirinya. Realitas ini ada penciptanya. Oleh karena itu, kita tidak dapat memperlakukan realitas tersebut seenak kita, terutama seyogyanya kita tidak merusak realitas tersebut, kecuali kita memiliki alasan-alasan yang dapat diterima berdasarkan patokan etika dan estetika tertentu. Menempatkan kembali realitas objektif yang diteliti atau dipelajari sebagai ciptaan Allah Yang Maha Pencipta adalah apa yang oleh Kuntowijoyo disebut sebagai proses transendensi. Menurut Kuntowijoyo, “Bagi umat Islam sendiri tentu transendensi berarti beriman kepada Allah s.w.t. (tukminuna billah)”.67 Bagi Ilmu Hukum Profetik, kiranya perlu dipikir ulang apa sebenarnya yang menjadi objek material ilmu hukum profetik itu dan bedanya dengan Ilmu Hukum pada umumnya. Untuk mengetahui hal ini, maka yang perlu dipertanyakan adalah apa sebenarnya yang menjadi hakikat dari hukum itu sendiri? Dalam Ilmu Hukum pada umumnya banyak asumsi dasar yang diikuti oleh para ilmuwan hukum untuk menjelaskan apa hakikat hukum itu. Menurut hemat penulis tentang hal ini dapat diusulkan bahwa hakikat hukum adalah kehendak Allah yang ditujukan kepada manusia untuk mencapai derajat manusia yang mulia sebagai khalifah. Hukum berfungsi sebagai sarana dan wahana manusia untuk mendapatkan ridho-Nya. Hukum Allah harus menjadi landasan etik bagi hukum ciptaan manusia. Hukum ciptaan manusia pada dasarnya adalah perlanjutan yang konsisten dari hukum Allah. Karena itu tegak dan eksisnya hukum-hukum ciptaan manusia dapat mendatangkan malapetaka bagi manusia dengan ekosistemnya, manakala tidak bersandarkan pada kehendak Allah. Hukum yang dibuat oleh manusia harus mencerminkan misi humanisasi, leberasi dan transendensi sebagai perwujudan dari etika profetik. 3. Asumsi Dasar tentang Disiplin Disiplin di sini dimaksudkan sebagai cabang ilmu. Disiplin profetik tentu saja merupakan disiplin yang berbeda, walaupun masih ada 67 Kuntowijoyo, Op.Cit. hlm.107. Bab 4 219 persamaan dengan disiplin ilmu pada umunya. Disiplin profetik adalah cabang ilmu yang mempunyai ciri profetik. Disiplin profetik di sini dapat dibangun dari disiplin ilmu pada umumnya, yang memiliki ciri profetik seperti ilmu kedokteran profetik, ilmu kehutanan profetik, ilmu teknik profetik, ilmu farmasi profetik, sosiologi profetik, Ilmu Hukum Profetik, psikologi profetik, antropologi profetik, dan seterusnya.68 Asumsi-asumsi dasar disiplin profetik ini tentu saja sebagian akan sama dengan asumsi dasar disiplin ilmu yang ada, tetapi sebagian yang lain tentu akan berbeda. Oleh karena masing-masing disiplin memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri, maka ekspresi ciri profetik ini juga berbedabeda dalam masing-masing disiplin, tetapi di situ tetap ada keprofetikan yang diturunkan dari sesuatu keprofetikan yang umum.69 Dengan mengikuti pola pembagian disiplin ilmu seperti itu, maka disiplin Ilmu Hukum Profetik, asumsi dasarnya dapat berasal dari ilmu hukum pada umumnya, akan tetapi sebagian lagi berasal dari asumsi dasar yang ada dalam Ilmu Hukum Profetik, yang tidak terdapat dalam ilmu hukum pada umumnya. Ini yang membedakan mana Ilmu Hukum yang umum dan mana Ilmu Hukum Profetik. 68 69 Heddy Shri Ahimsa-Putra. Op.Cit. Loc.Cit. 220 Landasan Epistemologi... BAB 5 LANDASAN AKSIOLOGI ILMU HUKUM PROFETIK A. Pengantar Oleh M. Syamsudin Landasan aksiologi dihadirkan di hadapan kita untuk memberikan pemahaman tentang kegunaan atau manfaat dari suatu ilmu. Hal-hal mendasar yang menjadi pertanyaan untuk dijawab terkait dengan aksiologi ilmu antara lain adalah untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dicari, dikembangkan dan dipergunakan dalam kehidupan kita? Bagaimana kaitan antara cara mencari, mengembangkan dan menggunakan ilmu tersebut dengan kaidah-kaidah moral? Apakah penentuan objek yang ditelaah oleh ilmu tersebut didasarkan pada pilihan-pilihan moral? Bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dengan norma-norma moral/ profesional? dan sebagainya. Dalam konteks ilmu hukum, landasan aksiologi ilmu dibutuhkan untuk memahami persoalan-persoalan keilmuan hukum yang berkaitan dengan masalah pengembanan hukum (rechtsbeoefening) itu sendiri. Pengembanan hukum adalah kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum di dalam masyarakat. Kegiatan tersebut mencakup kegiatan membentuk, melaksanakan, menerapkan, 222 Landasan Aksiologi... menemukan, meneliti, dan secara sistematikal mempelajari dan mengajarkan hukum yang berlaku. Pengembanan hukum itu dapat dibedakan antara pengembanan hukum teoretis dan praktis. Pengembanan teoretis dimaksudkan sebagai kegiatan akal budi untuk memperoleh penguasaan intelektual tentang hukum atau pemahaman tentang hukum secara ilmiah yakni secara metodis, sistematis-logis dan rasional. Berdasarkan tataran analisisnya (level of analysis) atau tingkat abstraksinya, pengembanan hukum teoretis dibedakan dalam tiga jenis, yaitu pertama, tataran ilmu-ilmu positip, yaitu tataran yang paling rendah tingkat abstraksinya, disebut ilmuilmu hukum; Kedua, tataran yang lebih abstrak tingkat abstraksinya disebut Teori Hukum, dan ketiga, tataran filsafat yang abstraksinya paling tinggi disebut Filsafat Hukum. Filsafat Hukum meresapi semua bentuk pengembanan hukum teoretis dan praktis. Pengembanan hukum praktis adalah kegiatan yang berkenaan dengan hal mewujudkan hukum dalam kenyataan kehidupan sehari-hari secara konkrit, yang meliputi kegiatan pembentukan hukum, penemuan hukum, dan bantuan hukum.1 Jika kita meninjau ke kondisi pengembanan hukum (rechtsbeoefening) di Indonesia saat ini, baik pengembangan teoretis maupun praktis, banyak sekali dimensi aksiologis yang membutuhkan perhatian dan pencerahan. Skema berikut menggambarkan bagianbagian dari pengembanan hukum yang perlu untuk mendapatkan perhatian. Baca Meuwissen. 1994. “Pengembanan Hukum” PRO JUSTITIA Tahun XII No.1 Januari 1994. hlm.61-81. Juga Meuwisen. 2007. Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum. Penerjemah Arief Shidarta. Bandung: Refika Aditama. Hlm. vii. 1 Bab 5 223 Pengembanan Hukum PRAKTIKAL Pergaulan dengan hukum dalam kehidupan nyata PENGEMBANAN HUKUM Kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum TEORETIKAL - Disiplin Hukum - Upaya memahami dan menguasai ukum secara intelektual - Bermetode logiksistematikal, rasional kritikal PEMBENTUKAN HUKUM - Penciptaan hukum positif PENEMUAN HUKUM - Distilasi kaidah dari dalam atuaran hukum dalam konteks penyelesaian konfliks BANTUAN HUKUM - Memulihkan keseimbangan kekuatan antar warga NORMATIF Persepektif internal objek ILMU-ILMU telaah: hukum HUKUM sebagao Objek telaah: Sollen-Sein tatanan hukum nasional dan EMPIRIKAL Internasional Perspektif eksternal TEORI (ILMU) HUKUM Objek telaah: tatanan hukum positif sebagai sistem PERUNDANG-UNDANGAN: Aturan umu PUTUSAN KONKRET - Ketetapan - Vonis TINDAKAN NYATA - Memulihkan keseimbangan jejuatan antar warga ILMU HUKUM: Ilmu praktikal normologik - Interpretasi dan sistematisasi bahan hukum - Teori Perundang-undnagan, Penemuan Hukum dan Argumentasi Yuridis AJARAN HUKUM - analisis pengertian hukum (concept of law) - analisis asas, kaidah, figur dan sistem hukum - analisis konsepkonsep yuridis (legal consept) - hubungan antar konsep yuridis HUBUNGAN HUKUM DAN LOGIKA - Teori Argumentasi Yuridis - Logika Deontik METODOLOHI FILSAFAT HUKUM - bagian dari dan dipengaruhi filsafat hukum - meresai Teori Ilmu Hukum dan Ilmuilmu Hukum - Objek telaah: hukum sebagai demikian (the law as such) - Pokok kajian dwitunggal pertanyaan inti: 1. landasan daya-ikat hukum 2. landasan penilaian keadilan dari hukum (norma kritik) PERBANDINGAN HUKUM SOSIOLOGI HUKUM Objek telaah: hukum sebagai sollen-sein SEJARAH HUKUM Objek telaah: hukum dalam konteks waktu ANTROPOLOGI HUKUM Objek telaah: hukum dalam konteks kultur PSIKOLOGI HUKUM AJARAN ILMU HUKUM - Epistemologi Ilmu Hukum - Metode Penelitian dan Penemuan Hukum - Struktur Berpikir Yuridis AJARAN METODE PRAKTEK HUKUM - Teori Pembentukan Hukum - Teori Penemuan Hukum 1. Teori Interpretasi 2. Kontruksi Hukum refleksi teoritikal kritikal terhadap saling mempengaruhi Sumber: Meuwissen, tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat hukum, terj. B.Arief Sidharta, 2007 224 Landasan Aksiologi... B. Paradigma Profetik Pendidikan Hukum2 dalam Pengembangan Oleh Jawahir Thontowi 1. Pendahuluan Model pendidikan dan pengajaran hukum yang telah berlangsung sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945, baik di Perguruan Tinggi Negeri/Swasta belum berhasil menciptakan lulusan yang mampu menjalankan tugasnya secara professional. Sindiran nyata, bahwa hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas bukan isapan jempol belaka. Mbok Minah di Banyumas harus dihukum 3 (tiga) bulan oleh hakim karena mengambil dua kakao. Di Cilacap, ada seorang laki-laki kurang ingatan terkena hukuman karena mengambil pisang. Sementara hakim tipikor membebaskan tersangka bupati-bupati koruptor lepas dari jerat hukuman. Ini gambaran kelam penegakan hukum yang akan semakin terasa jauh dari rasa berkeadilan, jika tidak ada lompatan, atau revolusi ilmu pengetahuan hukum (scientific legal revolution). Tentu saja mustahil dalam hukum ada revolusi, pendiri bangsa seperti Soekarno saja enggan ngajak revolusi dengan Sarjana Hukum. Situasi hukum demikian ini tidak lain karena hukum dipandang sebagai tool (alat) yang bebas nilai, salah satu sebabnya karena sistem pendidikan dan pengajaran hukum tidak dilandasi suatu paradigma profetik. Untuk menyikapi hal tersebut, Fakultas Hhukum UII mengagas ilmu hukum berparadigma profetik sebagai landasan pendidikan hukum tergolong ikhtiar yang mulia. Hal ini merupakan gerakan terobosan di tengah status quo pendidikan hukum, sekedar menyiapkan tukang-tukang yang memiliki kemahiran dan professionalitas tinggi (applied science), yang Disampaikan dalam Kegiatan Disksui Berseri “Menggagas Ilmu Hukum Berparadigma Profetik Sebagai Landasan Pengembangan Pendidikan Hukum” di Fakultas Hukum UII”, diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Kamis, 12 April, 2012, di Aula Kampus UII Jalan Cik Ditiro 1. Yogyakarta. 2 Bab 5 225 kebanyakan lahir Sarjana Hukum berkaca mata kuda (positivism doctrine) dan miskin penggunaan hati nurani (conscience). Fakta sejarah menunjukkan bahwa perkembangan ilmu sosial dan khususnya ilmu hukum, yang hendak menuju pada pemikiran paradigmatik diakui secara akademik dan kritis tidak mudah dicapai. Mengingat timbulnya berbagai tantangan, baik dari pendekatan pribadi seorang/sekelompok akademikus maupun dari pendekatan kelembagaan aktor Negara/non Negara (non-state actors). Apalagi jika paradigma yang diusung berkarakter Islam, tentu tantangan akademik dan politik semakin paripurna. Antara tantangan yang dihadapi dalam menggagas kerja besar dan mulia tersebut terkadang tidak sebanding dengan peluang-peluang tersedia yang telah dikaji mendalam dan kritis. Sebagaimana halnya pertanyaan yang timbul apakah Pusat Studi Hukum (PSH) telah dapat mengindentifikasi, memilih dan memilah persoalan dan jawaban dari dua kali pertemuan sebelumnya. Mohon maaf saya menggelitik model kerja dari penyelenggaraan diskusi yang satu ke diskusi yang lain belum terlihat langkah pencapaian.3 Hendaknya PSH, sembari melakukan pencarian dan pengumpulan bahan dan masukan seharusnya juga melangkah untuk dapat merumuskan berbagai inti masukan dengan kebutuhan konseptual dan praktikal pengembangan pendidikan dan pengajaran di Fakultas Hukum UII. Tidak mustahil akan menjadi kurang termanfaatkan jika masukan-masukan yang terasa berat tidak segera dimulai ditindaklanjuti dengan upaya mentradisikannya berbagai gagasan sederhana yang dapat segera direalisasikan. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dalam kesempatan yang mulia ini perkenankanlan untuk memberikan berbagai jawaban atas pertanyaan sebagai berikut. Suatu pertanyaan yang diajukan bukan Acara diskusi berseri ini telah dimulai sejak 12 Juni 2011 sd 12 April 2012, dan sampai saat ini tampaknya disuksi kita baru disuguhi wacana-wacana akademik, filosofis, epistiomologis dan juga teoretik yang tampak masih belum mengerucut pada luaran yang diharapkan. 3 226 Landasan Aksiologi... sekedar rasa ingin tahu curuosity, (cogito ergo sum), tetapi karena adanya kepentingan dan kebutuhan yang dinantikan kehadirannnya dalam sistem sosial dan pendidikan yang belum mmebebaskan dan mencerahkan kita sebgai bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat. Pertama, apakah makna dan manfaat paradigma dalam ilmu pengetahuan? Kedua, bagaimana penggunaan paradigma dalam ilmu sosial dan filsafat? Ketiga, apakah paradigma diakui dalam konteks negara Pancasila? Keempat, bagaimana paradigma profetik relevan dikembangkan di Fakultas Hukum UII yang sedang turut mengawal perjalanan bangsa dari Yogyakarta hingga jagad Indonesia Raya? 2. Makna dan Fungsi Paradigma Pencetus awal gagasan paradigma adalah Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolution, (1962) bertujuan menantang anggapan umum bahwa yang berlaku mengenai cara terjadinya perubahan ilmu. Masyarakat awam memandang bahwa kemajuan ilmu terjadi secara akumulatif. Setiap tahap kemajuan tanpa terelakan dibangun di atas kemajuan yang telah tercapai sebelumnya. Namun, Kuhn mengakui bahwa kemajuan memang penting dalam menghantarkan kemajuan ilmu, tetapi terjadinya perubahan besar tidak lain sebagai akibat revolusi atau perubahan sangat cepat. Secara sederhana, Kuhn merumuskan paradigma: sebagai (1) citra mendasar tentang apa yang menjadi masalah pokok ilmu di masa tertentu, (2) ilmu normal adalah periode akumulasi ilmu pengetahuan, dimana ilmuwan berkarya untuk mengembangkan paradigma yang dominan, (3) karya ilmiah tersebut tanpa terelakan akan melahirkan karya-karya baru yang tidak dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan sebelumnya, (4) tahap krisis akan terjadi ketika ketidakajegan (anomali) kian meningkat dan hanya akan terjawab dengan model revolusi ilmu (scientific revolution).4 Lihat Thomas Kuhn. 1962. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press. 4 Bab 5 227 Paradigma adalah gambaran fundamenetal mengenai masalah pokok dalam ilmu tertentu. Paradigma membantu dalam menentukan apa yang mesti dikaji, pertanyaan yang mesti diajukan, bagaimana cara mengajukannya, dan aturan apa yang harus diikuti dalam menafsirkan jawaban yang diperoleh. Paradigma adalah unit konsensus terluas dalam bidang ilmu tertentu dan membantu membedakan satu komunitas ilmiah (subkomitas) tertentu dari komunitas ilmiah yang lain. Paradigma menggolongkan, menetapkan, menghubungkan antara examplar, metode, dan instrumen yang ada di dalamnya. Lebih jauh Ritzer menegaskan bahwa sosiologi, sebagai ilmu berparadgima ganda timbul karena paradigma tidak akan mencapai titik optimal dalam sosiologi jika tidak didukung oleh tiga hal yaitu fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Masing-masing paradigma harus dianalsis oleh empat komponen paradigma. Fakta sosial akan menjadi paradigma jika di dalamnya terdapat (1) Examplar atau model, yang digunakan teoretisi fakta sosial contoh Karya Emile Durkheim, terutama dalam karyanya, The Rules of Sociological Method of Suicide. (2), Gambaran tentang masalah pokok, misalnya, teoretisi memusatkan perhatiannya pada fakta sosial yang disebut Durkheim sebagai struktur atau institusi sosial yang berkala luas, (3). Metode, besar kemungkian penganut paradigma ini, cara memperoleh menggunakan metode interviewkuesioner dan menggunakan perbandingan sejarah ketimbang metode lain. (4). Teori, teoretisi structural-fungsional cenderung melihat fakta sosial sama antara hubungan keteraturan dengan yang dipertahanakan oleh consensus umum. Sedangkan teori konflik, selalu melihat perubahan masyarakat dari segi kekacauan atau pertentangan sosial. 5 Paradgima definisi sosial, sebagaimana dianut oleh Max Weber, juga sama terdiri dari model, gambaran tentang masalah, metode, dan terori. Paradigma perilaku sosial, penganut paradigam ini, adalah (1) model aliran behaviourisme, (Psikologi) BF Skinner (2) Gambaran permasalahan, Pemaparan lebih komprehensif dapat dilihat George Ritzer and Doglas Goodman. 2003. Modern Sociological Theory. (Six Edition), McGraw-Hill. Mariland. USA. A.15. 5 228 Landasan Aksiologi... perubahan didasarkan adanya reward and punishment. (3) Metode, experiment (4) Teori Behaviorisme Sosial. Namun, ketiga paradigma, fakta sosial, definisi sosial dan perilaku sosial tidak cukup oleh karena dapat membawa pada hasil kurang objektif, manakala tidak dibantu analisis sosial. Itulah sebabnya, pengikutnya Ritz dan Nash, mencoba mengajukan suatu paradigma sosiologi integratif. Dari kacamata sosiologi status, fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial yang dalam zamannya masing-masing dipandang valid dan relevan, di kemudian hari ternyata tidak sempurna. Hadirnya model berpikir lain ada seperti paradigma sosiologi integratif, menunjukkan proses penyempurnaan akan berakhir dalam relatifitas. Talcot Parson menggunakan istilah paradigma dalam kaitannya dengan sistem sosial, diakui selalu berubah dan berkembang karena dipengaruhi oleh terjadinnya perubahan sosial. Menurut Parson, tanpa adanya kesepahaman yang baik dari pengetahuan, suatu paradigma tidak akan pernah menjadi suatu yang mungkin. Namun, pengetahuan tersebut hanya untuk menjawab pemecahan persoalan empiris, dan secara fragmentaris juga tidak sempurna. Untuk itu, dalam konteks dengan kemanfaatan paradigma, Parson mengajukan dua hal untuk menyempurnakannya dengan dua hal. Pertama, paradigma membantu untuk memobilisasi setiap pengetahuan hukum yang kita memiliki utamanya terkait dengan persoalan relevan yang dijelaskan dalam proses sistem sosial. Kedua, paradigma memberikan kita suatu pedoman untuk suatu ketegasan permasalahan yang signifikan untuk suatu penelitian sehingga pengetahuan dapat kita kembangkan. Dengan demikian, menurut Parson, in so far as it does not directly incorporate knowledge of laws, then, the paradigm is a set of canons for the statement of problems, in such terms as as to ensure that the answers to the question asked will prove to be of generalized significance, because they will state or imply definite relations between the fundamental variables of a system.6 Pandangan Talcott Parsons, telah memulai mengarahkan kajian paradima dengan menghubungkannya dengan persoalan hukum. Lihat karyanya, Talcott Parsons. The Social System: The Major Exposition of the Author’s Conceptual Scheme for the Analisis of the Dinamics of the Social System. 6 Bab 5 229 Dalam sosiologi, paradigma tersebut menjadi penting tidak saja berkaitan dengan cara meperoleh fakta, data dan informasi lainnya dalam penelitian, akan tetapi lebih utama paradigma dipergunakan hendaknya melibatkan kekuatan analisis untuk mencegah kejadian penyimpangan yang subjektif. Kata kunci Parson, bagi upaya menjelaskan ilmu sosial dengan hukum tampaknya tidak secara otomatis dapat berkaitan dengan hukum. Tetapi, paradigma lebih dipahamkan sebagai sekumpulan nilai-nilai suci (canons) untuk suatu persoalan mendasar dalam penelitian yang tidak parsial. Itulah sebabnya, mengapa Fred N. Kerlinger dalam karya monumentalnya, Foundations of Behavioral Research, (second edition) menempatkan pembahasan paradigma dalam bagian, Prinsip-Prinsip Analisis dan Penafsiran (Principle of Analyses and Interpreation).7 Karena itu, menurut Kerlinger, suatu analisis dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan pengelompokan, pengaturan atau penyusunan secara tertib, memberikan makna, dan melakukan peringkasan dari data, fakta untuk memperoleh suatu jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan. Adapun maksud dari analisis yaitu menyederhanakan data yang dapat dipikirkan dan diberikan penafsiran, sehingga hubungan antara persoalan penelitian dapat dikaji dan dibuktikan secara nyata atau faktual. Mengapa akademisi dalam penelitian penting mengedepankan paradigma (1) penelitian akan dapat mengetahui seberapa jauh kerja konsep, teori, pertanyaan serta hipotesis dapat dijawab. Dengan cara itulah, peneliti dapat melihat, apakah data dan nalisisnya dapat menjawab permasalahan penelitian (2). Paradigma digunakan sebagai tool of analyses yang bermanfaat dalam memahami tingkat hubungan antara suatu ajaran dengan perilaku msayarakat. Pendidikan agama meningkatkan karakter moralitas anak-anak. Karena itu, pendidikan agama telah didefinisikan sebaga suatu unsur panutan dalam bagi anakLihat secara lengkap dalam Fred N. Kerlinger. 1973. Foundations of Behavioral Research, (second edition). Holt, Rinehart and Winston. London. P.134-8. 7 230 Landasan Aksiologi... anak di sekolah. Hubungan antara tingkat kejujuran, dan ketidakjujuran ditentukan selain oleh pelajaran agama, adanya tauladan, pengawasan publik, dan frekuensi tingkat keseringannya. (3), paradigma dapat menuntun secara langsung penelitian dalam melakukan pengujian atas hipotesis. Sebelum lebih jauh menempatkan paradigma dalam dunia lebih populer, makna yang lebih kurang sama digunakan istilah, kerangka teoretis (theoretial framework), kerangka konsptual (Conceptural frameework), kerangka pemikiran (frame of thinking), orientasi teoritis (theoretial orientation), atau sudut pandang (perspective), atau pendekatan (approach). Ahimsa-Putra mendefiniskan paradigma, sebagai seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan dan menjelaskan kenyataan dan/atau masalah yang dihadapi.8 Pemikir Ilmu sosial, sering menggunakan mensintesiskan gagasan Ilmu sosial profetik, kontribusinya dirasakan lebih relevan ketika belantara pemikiran paradigmatik menjadi lebih disederhanakan. Setidaknya ada enam komponen yang diformulasikan untuk dapat memahami paradigma dalam ilmu sosial, termasuk dapat diorientasikan ke dalam pemikiran dan pengembangan ilmu hukum. Hal tersebut antara lain (1) adanya asumsi dasar (dalil) kritis yang membimbing ilmuwan dalam mengawali pemikirannya. (2), etos atau nilai-nilai yang telah menjadi kepercayaan mendasari timbulnya berbagai permasalahan (3), model atau analogi yang digunakan sebagai peneliti dalam membimbing penelitian untuk mencari jawaban atau keingintahuannya (4), pemunculan permasalahan yang handal dan wajib dirumuskan, apakah sebagai pemenuhan atas hasrat ingin tahu, ataukah karena ada keperluan dan kebutuhan (5), adanya teori atau konsep-konsep pokok, sebagai pisau analisis terhadap (fakta sosial, definisi sosial dan perilaku sosial), dan (6) Adanya metode Heddy Ahimsa-Putra. 2001. “Paradigma Profetik: Sebuah Konsepsi. Disampaikan dalam Diskusi Pengembangan llmu Profetik 2011, diselenggarakan leh Fakultas HukumUII di Yogyakarta, 18 November 2011. Hlm. 3. 8 Bab 5 231 penelitian baik jenis kuantitatif (luas, besar, berat, jumlah, dan frekuensi,), maupun jenis kualitatif (nilai, pandangan hidup), kepribadian, norma, kriteria, keagamaan, kebiasaan, kesopanan, dan kesusilaan.9 Penggunaan paradigma dalam pendekatan ilmu politik, khususnya hubungan internasional telah berlangsung, penggunaan paradigma dikaitkan bukan sekedar untuk suatu analisis yang dapat melahirkan suatu hasil analisis yang objektif, melainkan sebagai alat memprediksi ke depan. Karya Samuel Huntington dengan jelas memperlihatkan bahwa paradigma digunakan tidak untuk selamanya, tetapi terbatas hanya untuk beberapa dekade saja. Ketika paradgima peradaban digunakan untuk melihat hubungan Barat dan Timur, serta Utara dan Selatan maka abad kedua puluh suasana masyarakat dunia telah mengalami perubahan. Apa yang dikatakan Samuel Huntington tidak diragukan ketika kata paradigma digunakan sebagai suatu pendekatan dalam memprediksi tatanan politik dunia. A civilizational paradigm thus set forth a relatively simple, but not too simple map for understanding what is going on in the world as the twentieth century ends. No paradigm, however, is good forever. The Cold War model of world politics was useful and relevant for forty years but become absolete e in the late 1980 and at some point the civilizational paradigm will suffer a similar fate. .. Paradigm also generate predictions, and a crucial test of a paradigm’s validity and usefulness is the extend to which the prediction derived from it turn out to more accurate than those from alternative paradigms.10 Dengan kata lain, baik dalam pendekatn ilmu sosial dan juga politik internasional, penggunaan paradigma selalu dikaitkan dengan suatu cara, the way, manhaj, yang digunakan untuk memecahkan, menjawab krisis akibat tuntutan dan perubahan dengan menciptakan asumsi landasan terpadu terdiri dari asumsi, nilai, teori, konsep, metode penelitian dan analisis yang dioperasionalisasikan secara terpadu. Ibid. Menarik pandangan Samuel Huntington dalam penggunaan paradigma sebagai suatu pendekatan dlam memahami perubahan peta politik politik dunia kontemporer. Samuel Huntington 2002. The Clash Civilizations and the Remaking of World Order. London: WC2B. An Imprint of Simon Suchter UK. 9 10 232 Landasan Aksiologi... 3. Paradigma dan Filsafat Ilmu Hukum Kelahiran peraturan hukum, sebagaimana dirumuskan di Jerman dan Perancis, terdiri dari hukum tertulis (written law), yang terkadang teks yang ada jauh di kemudian hari tak memiliki kesesuaian. Paradigma dalam ilmu sosiologi berfungsi sesuai perkembangan zaman adalah tampak jelas bahwa paradigma tersebut didukung oleh fakta sosial, definisi sosial, perilaku sosial dan analisis. Apakah sama kiranya jika ilmu hukum tidak memiliki kemampuan fungsional responsif juga harus menggunakan pendekatan paradigmatik sebagaimana dibicarakan dalam kebanyakan ilmu sosial. Tampaknya, Jurgen Hubermas memberikan isyarat bahwa perkembangan hukum di Jerman dan juga Perancis, tidak luput dari situasi krisis. Sejak perang Dunia II, Jerman telah menerapkan sistem hukum tertulis. Namun karena perkembangan sosial dimana kaum berdasi telah mendominasi proses pembuatan hukum di tingkat legislasi, maka persoalan fungsi dan tujuan hukum, utamanya telah menggeser keadilan menjadi bagian yang dapat diperoleh masyarakat pada umumnya. Peraturan hukum, teori hukum yang diterapkan dalam kekuasaan termasuk sistem ajudikasi di pengadilan terkadang keluar dari norma hukum yang seharusnya. Jika kondisi hukum dan kebanyakan masyarakat, baik di masyarakat barat pada umumnya telah bergeser, maka sesungguhnya krisis tersebut telah menenggelamkan ilmu hukum. Krisis kekuasaan dan juga krisis hukum yang anarkis dan diktatorshipnya, Hitler tidak membuat ahli-ahli hukum diam untuk mengubah model pengembangan hukumnya. Peraturan hukum berbentuk Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan berbagai peraturan yang tertulis berseberangan antara Text dan Konteks. Itulah kemudian, sekitar 1931, Otto Kahn-Freund melakukan pengujian terhadap ideal masyarakat dari suatu Mahkamah Agung (Reichsarbeitsgericht). Kemudian dua dekade berikutnya, Franz Wiecker, memperkenalkan konsep yang hampir senada disebut “social model” yang mejelaskan suatu tujuan deskriptif untuk mencoba membuat suatu Bab 5 233 pemikiran paradigma hukum yang liberal dalam kelompok kitab perundangan-undangan kelompok hukum perdata. Adapun maksud dan tujuan Franz adalah untuk membuka model sosial yang memberikan keteraturan hukum dan bagaimana model sosial mampu melakukan perubahan dalam suatu rekayasa rahasia, dengan mengemasnya ke dalam kesusatraan, kemanusiaan, dan keberlanjutan konsep dari suatu tradisi ilmiah.11 the opaoque and inconsistent structure of such a legal order has thus stimulated the search for a new paradigm beyond the familiar alternatives. The tentative answers that readers are left with ant the end of Dieter Grimm’s study “The Future of the Constitution typify the aporias afflicting contemporary debates.12 Dengan kata lain, perubahan sosial termasuk pencapaian ke arah masyarakat yang sejahtera secara sosial dan ekonomi, dari pengalaman Jerman adalah perubahan paradigma, dengan melakukan suatu amandemen Basic Law atau UUD (Grundgesetz). Apakah perbedaan pemahaman terhadap konstitusi dapat menyerap kehilangan keabsahannya, ataukah apakah suatu UUD akan menjadi bagian dari ketertiban yang terpisah, akan tetap membuka suatu pertanyaan akan pentingnya hukum yang transformatif untuk dapat melawan teks yang dapat ditafsirkan secara lebih proporsional. Kontribusi pandangan sosioologi terhadap hukum adalahh Santos seorang Profesor Sosiologi dari Portugal, dan termasuk Profesor yang sering berkunjung ke Universitas Wisconsin Law School. Dalam sosiologi dan teori-teori sosial lainnya, mengedepankan suatu tesis yang Kajian paradigmatic hukum di Jerman juga menujukan kesamaan dengan pandangan Thomas Kuhn, Jurgen Habermas dalam karyanya, Between Facta and Norms: Contribution to a Discourse Theory of Law and Democracy (translated by William Rehg). Polity Press Oxford, UK. 1997:390. Perubahan ilmu sosial pada umumnya sosiologi, dan hukum pada khususnya meperlihatkan gejela yang sama. Selain dalam ilmu sosial stagnasi merupakan lawan status quo, kebekuan ilmu pengetahuan termasuk fungsi dan tujuan hukum yang hanya memerkuat kekuasaan dan tidak peduli pada kesejahteraan rakyat, maka konsep model sosial, atau paradigma diperlukan untuk terjadinya suatu perubahan yang cepat. 12 Ibid. Hlm. 391. 11 234 Landasan Aksiologi... melakukan terobosan dalam dunia modern dan kehadiran suatu paradigma baru, adalah suatu maksud dari buku yang secara keseluruhan mengidentifikasi beberapa unsur perundang-undangan dari suatu gerakan hukum postmodernis. Lahirnya paradigma baru untuk memahami hukum tersebut antara lain disebabkan oleh beberapa alasan: (1) bidang hukum dalam masyarakat kontemporer dewasa ini merupakan suatu sistem dunia yang secara keseluruhan menjadi sangat kompleks dan lebih kaya dengan peta-peta kondisi hukum sebagaimana telah dirumuskan oleh para pemikir teori liberal; (2) setiap bidang hukum saat ini merupakan konstelasi dari sistem hukum berbeda dan beroperasi dalam lingkup lokal, nasional, antara lintas negara dalam ruang dan waktu berbeda pula; (3) dan akhirnya, bahwa hukum memilki dua sifat pengatur dan bahkan berpotensi memaksa dan berpotensi emansipatoris. Lebih dahsyat lagi adalah suatu model perubahan yang normal dan rinci, bagaimana suatu peraturan hukum memiliki potensi berubah secara perlahan-lahan (berevolusi), apakah terhadap pengaturan atau emansipasi, yang sesungguhnya tidak berkaitan dengan konsep autonomi reflektif hukum, tetapi lebih di pengaruhi oleh karena mobilisasi politik dari persaingan berbagai tekanan.13 Manakala pengaruh globalisasi terhadap ilmu hukum tak terelakkan maka paradigma menjadi penting dan utama dalam menjembatani ilmu hukum dan peristiwa sosial yang terkadang paradoksial. Dari kajian perbandingan filsafat hukum, Erlyn tampaknya tidak memberikan spekulasi lebih jauh terhadap perumusan paradigma profetik. Netralitas Erlyn dengan mengacu pada Guba dan Lincoln, mengedepankan empat paradigmatik hukum, (1) paradigma positivisme yang terdiri dari: aliran hukum filosofis, aliran hukum teologis, dan aliran hukum alam, (2) paradigma post-positivisme, terdiri dari aliran hukum realis, aliran hukum behavioralisme, strukturalisme dan Lihat William Twinning. 2000. Globalization and Legal Theory. Santos dan Haack, and Calvino, Globalization, Post-modernism, and pluralism. Butterworth. London. P. 198 13 Bab 5 235 funsgionalisme dan strukturalisme-funsgioanlisme, aliran hukum dan masyarakat dan aliran sosiologi hukum, (3) paradgima teori kritis, meliputi teori hukum kritis, dan studi hukum kritis, dan teori hukum feminis, (4) paradigma konstruktivisme, meliputi aliran hukum simbolis interaksionis, aliran hukum fenomenologis.14 Atas perdebatan keempat paradigmatik yang tak mengakhiri antagonistik tersebut, Erlyn mencoba mengkaitkannya dengan model diskresi. Menurut Erlyn, persoalan menjangkitnya diskresi dalam penegakan hukum dapat melekat pada pengambilan keputusan. Pentingnya diskresi dalam memahami dan menafsirkan hukum adalah menjembatani jurang pemisah antara tinjauan filsafat yang satu dengan yang lain. “Betapapun pembumian dilakukan, tidak lantas dapat menjadi tinjuan filsafat maupun filsafat hukum sepenuhnya kongkrit.” Diskresi dipahami sebagai kemerdekaan dan/otoritas seseorang/kelompok orang/ institusi, yang secara bijaksana dan dengan pertimbangan untuk membaca, menerjemahkan dan/atau menafsir, meneliti, memilih dan memilah, serta membuat keputusan dan/atau mengambil tindakan hukum tertentu yang dipandang paling tepat. Pentingnya kajian Erlyn, paradigmatik terhadap diskresi yaitu memberikan kemampuan mengurai dan mendudukan serta memecahkan kompleksitas persoalan hukum termasuk perdebatan diskresi dalam masyarakat. Meski secara tidak disadari, kajian paradigmatik diskresi Erlyn, memberikan kontribusi pada kemungkinan lahirnya gagasan paradigma profetik. Secara eksplisit, Erlyn mengemukakan pentingnya paradigma antara lain, bahwa tanpa kajian paradigmatik, jurang pemisah di antara berbagai aliran Filsafat Hukum akan menjadi persoalan hukum, sepertinya misalnya diskresi, tak kunjung terselesaikan. Melalui kajian paradigmatik, pengertian yang baik dan benar mengenai derajat perbedaan yang ada di antara para pakar, praktisi dan pengamat hukum dalam memahami dan Lihat dalam Power Point karya Erlyn Indarti. Paradigma dan Ilmu Hukum: Suatu Telaah Filsafat Hukum Tentang Diskresi. Disampaikan dalam Diskusi Berseri, diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum, FH UII, 16 Juni 2011. di Aula Fakultas Hukum UII, Jalan Taman Siswa 158. Yogyakarta. Hal 16-24 14 236 Landasan Aksiologi... menggunakan diskresi dapat dicapai. Komparasi paradigmatik berfungsi untuk mengurai, mendudukkan pada tempatnya, serta memecahkan kompleksitas persoalan hukum, termasuk perdebatan tentang diskresi.15 Menempatkan diskresi dalam pemaparannya, lebih menekankan pada metode analisis tampaknya mengarah pada pembentukan tradisi berpikir hukum berparadigma profetik. Hal ini utamanya terjadi ketika dikaitkan dengan konsep tradisi kebebasan berpikir dalam, yakni Ijtihad (akan diulas di bagian akhir tulisan ini). Muhammad Abduh sebagai modernisme Islam pernah mengatakan ketinggalan peradaban Islam karena kebebasan pintu ijtihad was closed. Kebebasan bernalar hukum yang telah dikembangkan oleh aliran hukum Islam (Fuqoha) yang telah menapakan kejayaannya dalam bidang filsafat hukum Islam.16 4. Pemikiran Hukum Paradigmatik Pancasila Dalam konteks ke-Indonesiaan, pendekatan paradigmatik tidak dapat lepas dari kehadiran filsafat hukum Pancasila. Pandangan Bernard Arief Sidharta terkait dengan realitas hukum di Indonesia masih relevan dikedepankan. De facto, ilmu hukum yang diemban di Indonesia sebagaimana diajarkan dalam pendidikan hukum dan dipraktikan para praktisi hukum in de diepsten grond masih berkiprah dalam kerangka paradigma ilmu hukum anno 1924. Ilmu hukum hanya sebagai eksemplar normologi yang mempelajari hukum hanya sebagai tatanan aturan hukum positip seperti diajarkan Hans Kelsen dengan Reine Rechtslehre dan aliaran hukum positip lainnya. Menurut Arief Sidharta, paradigma hukum nasional tersebut mengacu pada cita hukum, Pancasila sebagai pangkal tolak dari keyakinan bahwa alam semesta dengan segala isinya, termasuk manusia, yang sebagai suatu keseluruhan terjalin secara harmonis, diciptakan oleh Tuhan. Hakikat hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat berakar pada gagasan rasa, karsa, cipta dan fikiran dari masyrakat itu 15 16 Ibid., Erlyn. VI. 2011. 22-24. Lihat Ahmad Hasan. 1985. IJMA. Bandung: Penerbit Pustaka. Hlm. 275. Bab 5 237 sendiri. Cita hukum menurut Arief, adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum dan persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya, terdiri dari tiga unsur, keadilan, kehasilgunaan, dan kepastian hukum. Dalam cita hukum Pancasila berintikan ajaran: Ketuhanan Yang Maha Esa, Penghormatan atas martabat manusia, wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara, persamaan dan kelayakan, keadilan sosial, moral dan budi pekerti yang luhur, dan partisipasi dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan publik.17 Dalam konteks, paradigma hukum nasional yang mangcu pada cita hukum, Pancasila, maka ilmu hukum tidak bebas nilai (no-free value). Dalam kajian filsafat secara khusus, Kaelan mengatakan bahwa paradigma yang berkembang menjadi suatu terminologi yang mengandung konotasi pengertian sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asa arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan serta proses dalam suatu bidang kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Secara filosofis, di Indonesia kedudukan Pancasila sebagai paradigma kehidupan kenegaraan dan kebangsaan mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek kehidupan kenegaraan dan kebangsaan termasuk sistem hukum Indonesia, mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam hubungan dengan ilmu pengetahuan di Indonesia, termasuk ilmu hukum dipastikan mengaut pandangan “value bound” . Karena itu, jika nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan hukum akan dikembangkan ke dalam filsafat ilmu maka dasar ontologis, epistimologis, serta dasar aksiologis hendaknya menjadi pilar utamanya. Pertama, ilmu pengetahuan hukum harus memiliki dasar ontologis, bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dengan nilai religius, nilai kodrat Lihat pemikiran Bernard Arief Sidharta. 2000. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum. Bandung: Penerbit Mandar Maju. Hlm. 185. Bandingkan K.N. Jaya Tikele, bahwa sistem hukum timur, tidak sekedar terdiri dari penalaran hukum semata, tetapi mengutamakan, nilai harmoni, yaitu status dari hukum yang benar atau salah. Lihat Jayatikele dalam Dr. R. H. Hickling, Major Legal Systems. Centre for Southerns Asian Law Faculty of Law, Northern Teritorry. 1996 17 238 Landasan Aksiologi... manusia, nilai persatuan dan kebhinekaan Indonesia, nilai demokrasi dan nilai keadilan dalam hubungannya dengan masyarakat dan bangsa Indonesia. Kedua, aspek epistimologi yaitu, menyangkut tentang hakikat sumber pengetahuan, kebenaran pengetahuan, cara mendapatkan pengetahuan, karenanya, hukum tidak dapat hanya dipandang secara ontologis sebagai produk penguasa semata dan hukum kodrat, akan tetapi didasarkan kepada nilai-nilai religius, Pancasila, sebagai cita hukum abstrak, dengan mengakomodir, hukum formal modern, dan mengakomodir sumber hukum agama, dan hukum adat, sebagai local wisdom, dikembangkan metode eklektif kritis. Ketiga, aspek aksiologis terkait dengan dasar-dasar etika dan moral yang harus menjadi dasar perilaku para praktisi hukum dalam menjalankan tugas profesionalnya. Keberadaan ilmu hukum Indonesia yang terikat dengan dasar filosofis Pancasila, maka penegakan hukum yang berkeadilan tidak mungkin dapat dicapai tanpa perilaku yang dibimbing oleh etika dan moralitas, baik-buruk, atau benar-salah.18 Dengan demikian pendekatan filsafat hukum sebagaimana diuraikan di atas, mengantarkan pada suatu keniscayaan bahwa paradigma ilmu hukum Indonesia hendaknya mengacu pada nilai-nilai dasar Pancasila. Di dalam filosofi Pancasila bukan saja mengandung nilai-nilai dasar, yang mendorong adanya karya, cipta, karsa, dan rasa dengan fungsi pemelihara harmoni antar hubungan antara Pencipta, alam, manusia, dan isinya, tetapi juga kerangka acuan filsafat yakni ontologi, epistimologi, dan aksiologi berada dalam suatu ikatan nilai tidak dapat ditawar. Pendekatan filosofis, Kaelan telah menggambarkan secara komprehensif tentang paradigma ilmu hukum yang mengacu pada dasar filosofis Pancasila, dengan mengaitkannya pada tiga pilar ilmu pengetahuan (ontologism, epistimologis dan aksiologis). Fungsi Pancasila sebagai Paradigma Hukum dalam Penegakan Hukum Konstitusionalitas Indonesia. Kaelan. 2011. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakan Konstitusionalitas Indonesia. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dengaan Universitas Gadjah Mada. Hlm. 50-107 18 Bab 5 239 5. Paradigma Profetik dalam Pengembangan Ilmu Hukum Untuk pengembangan ilmu hukum secara khusus penulis belum menemukan kajian paradigma profetik. Terkait dengan paradigma profetik, sebelumnya menjadi relevan untuk mengunakan bagaimana peran agama-agama besar dalam mempengaruhi perkembangan ilmu hukum. Paradigma profetik dapat didekati dari pendekatan dekonstruktifisme, suatu tulisan tentang Pengembangan Ilmu Hukum Berbasis Religious Science,19 yang menggagas tentang pentingnya mendudukan ajaran agama dalam perkembangan sejarah pembentukan pemikiran ilmu hukum. Situasi ini timbul kesamaan kepedulian mengingat berbagai paradigma kapitalistik yang melanda dunia, berakhir dengan hanya memuaskan kelompok tertentu dan menyengsarakan kelompok lain, khususnya kelompok masyarakat marjinal. Pentingnya pendekatan pengetahuan keagamaan (Religiousitas Saints) dalam memahami hukum fenomenologis tidak lain disebabkan karena terjadinya kekosongan (void) atau terjadinya mata rantai pemikiran hukum positivistik gagal memerankan fungsi dan tujuannya yaitu keadilan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara lebih komprehensif.20 Tidaklah naif jika kita memulai menyusun kembali pola pikir dengan menelusuri sejarah pertumbuhan ilmu hukum dengan menempatkan peran signifikan agama dalam peradaban Yunani, Romawi, Islam dan peradaban moderen, dialektika perkembangan ilmu hukum. (1) Terlepas pro-kontra, kontribusi agama-agama samawi dalam Jawahir Thontowi. 2011. “Pengembangan Ilmu Hukum Berbasis Religious Science: Dekonstruksi Filosofis Pemikiran Hukum Postivistik”. Makalah disampaikan dalam Kuliah Tamu di Paskasarjana Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang., diselenggarakan 13 Agustus 2011. 20 Jazim Hamidi, merupakan pioner muda yang mencoba melakukan dekonstruksi berpikir hukum, melalui pengkajian filsafat ilmu dengan program doktor S3 Fakultas Hukum Brawijaya, Malang. Buku yang berjudul Religiousitas Sains: Meretas Jalan Menuju Peradaban Zaman (Diskusi Filsafat Ilmu). Kumpulan tulisan mahasiswa S3 di bawah asuhan Dr. Jazim. M. Penerbit UB Press. Malang. 2010 19 240 Landasan Aksiologi... kontruksi ilmu pengetahuan hukum jelas memperlihatkan bukti nyata sebagaimana dikemukakan oleh Plato, Cicero, J. Berman, dan juga Benedict Ruth. (1) agama secara utuh, dan/atau sebagai budaya merupakan sistem nilai karena selain dapat berfungsi sebagai pedoman yang mengandung nilai-nilai universal kebenaran dan keadilan. (2) peran Agama dalam hukum internasional tidak dapat dinafikan ketika nilainilai agama yang universal tumbuh dan berkembang melintas negerinegeri kelahirannya. Ada marco Polo dari Spanyol dan ada juga Ibnu Baituta dari Africa, melakukan pelayaran luar biasa adalah fakta globalisasi. Vatican di Italia atau Roma bagi umat Kristiani dan Katholik, Mekkah di Saudi Arabia bagi umat Islam, dan India bagi masyarakat Hindu, Konghucu/Konfucianisme bagi masyarakat China telah menujukan wajah penduduk dunia pluralistik, termasuk dalam sistem hukumnya. (3) agama di sebagian negara-negara Muslim telah menjadi agama sebagai ideologi negara yang dimuat dalam konstitusi dan juga terdapat negara-negara Muslim yang tidak menjadikan agama sebagai agama negara. (4) tidak kalah pentingnya ketika masyarakat belum memiliki negara, agama telah menjadi pengganti hukum (legal substitution) yang dipandang sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat jauh lebih efektif daya lakunya karena masyarakat merasa lebih dekat dan falimiar dengannya ketimbang peraturan hukum undang-undang buatan negara.21 Sebaliknya kegagalan hukum nasional yang abai akan nilai-nilai agama suatu masyarakat juga timbul upaya memformalkan hukum yang cenderung tenggelam sebagaimana living law. Sejalan dengan itu, krisis yang menecemaskan para pemikir Barat, juga diakui oleh Mohammad Zaki Kirmani. Seorang, Direktur Center for Science Studies, Aligar University, India. Krisis yang timbul disebabkan oleh model dominan ilmu pengetahuan Barat. Pertama, berkaitan dengan adanya dikotomi dalam filsafat dan metode kajian dan pandangan Lahir Perda-perda Adat sejumlah 106 dan juga Perda-perda Syariat Islam lebih dari 164 perda di berbagai kabupaten, menunjukkan ketidakmampuan sistem hukum nasional yang unifikasi menjawab nilai-nilai yang lebih berkarakter lokal dan religius. 21 Bab 5 241 terhadap obyek yang sedang dikaji, dan yang lainnya berkaitan dengan keadaan masyarakat tempat tumbuh dan berkembangnya ilmu pengetahuan. Terkait dengan persoalan objek kajian bersifat holistik, menandakan adanya keterkaitan dan ketergantungan dengan berbagai bentuk makhluk yang ada. Namun, menjadi hal yang tidak dapat dipahami ketika proses penentuan kebenaran dengan memberikan pembenaran hanya dengan menggunakan suatu metode yang masih didasarkan pada filsafat yang secara fragmentaris dangat penting masalahanya. Kedua, krisis yang timbul dari luar terhadap ilmu pengetahuan barat saat ini terkait dengan struktur nilai masyarakat dimana ilmu pengetahuan terus tumbuh dan mekar. Dalam pandangan Zaki Kirmani, keunikan ilmu pengetahuan barat memiliki empat dimensi yang sekaligus menujukan ketidakkonsistenannya. Misalnya, ilmu pengetahuan telah memperlihatkan kemanfaatannya begitu besar untuk menjawab suatu persoalan-persoalan yang bertentangan dengan masyarakat dewasa ini. Misalnya, suatu penyelesaian atau persoalan berkaitan dengan pertanian, pemeliharaan kesehatan, komunikasi dan transportasi, telah memberikan begitu banyak kepuasan, tetapi dalam kelangsungannya tidak dilestarikan. Ilmu pengetahuan telah memberikan pelayanan dan menyediakan kekuasaan dan dunia kontemporer saat ini karena adanya kerjasama dengan para politisi, tetapi mengapa mereka tidak mampu menyingkirkan urusan militer ke dalamnya. Gagasan Zaki Kirmani sesungguhnya mengacu pada Maududi dan Sayyed Qutub, tidak lepas dari keharusan umat Islam, menerima berbagai hal dari ilmu pengetahuan Barat, seharusnya diuji dengan suatu pengetahuan kritis yang berkesesuaian dengan Alqu’an.22 Mohammad Zaki Kirmani, juga menghubungkan para sarjana Muslim memberi dan berkontribusi fundamental dalam mencari jalan Pandangan Mohammad Zaki Kirmani penting untuk dikemukakan, selain tergolong telah mengembangkan penggunaan dalam kontkes Islam dan Ilmu Pengetahuan. Islamic Science. Moving oward a New Paradigm, in Ziauddin Sardar (Editor). 1989. An Early Crescent: The Future of Knowwledge and the Enironment in Islam. London and New York: Mansel. Hlm.158 22 242 Landasan Aksiologi... keluar dari segi Islam untuk model pengembangan ilmu di Barat. Seyogyanya alternatif ini masih belum mendapatkan pengakuan penuh. Namun, beberapa aspek tentang Islam telah menarik perhatian dan memberikan kebanggaan bagi Barat dan Timur. Misalnya, aspek etika begitu melekat pada ilmu pengetahuan Islam, tampaknya mendapatkan pembenaran dari pemikir Barat Mereka mengakui ketiadaan etika dalam model Ilmu pengetahuan Barat. Karena akar ilmu pengetahuan bebas nilai (free value) menurut Mohammaf Zaki Kirmani, untuk mencapai kemajuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam, para intelektual Muslim kontemporer hendaknya memusatkan perhatian terhadap isu-isu yang relevan dengan ilmu pengetahuan Barat, dalam pandangan Islam. Ahimsa Putra, hasil bacaan saya terhadap tulisannya tergolong yang komprehensif. Tidak saja dalam membedah pemaknaan terhadap konsep paradigma yang digunakan dalam ilmu sosial budaya itu sendiri. Tetapi, juga mengedepankan pemikiran awal, mas Kuntowijoyo tentang pemikiran sejarah sosial yang profetik. Karena itu, gagasan Kunto bukan islamisasi pengetahuan, tetapi menjadi ’Pengilmuan Islam’, dari reaktif menjadi proaktif.23 Di balik pemikiran Kunto, dua nama seperti Muhammad Iqbal dan Roger Graudi telah mengilhami pola pemikiran Kunto tentang ilmu-ilmu sosial profetik. Mengacu pada sintesis tersebut, Ahimsa-Putra secara lebih eksplisit bahwa paradigma profetik dalam ilmu sosial dapat dikemukakan. Sebagai langkah awal, ia berangkat dari pemikiran Kunto yang paling awal, meski masih jauh dari sempurna. Dalam pemikiran Kunto sebagai sejarawan sosial, menempatkan Islam sebagai sumber nilai (etos). Karena itu, pengembangan paradigma Islam merupakan langkah pertama yang Sepertinya pandangan Kuntowijoyo tentang paradigma propetik tidak jauh dari sifat-sifat universal para nabi-nabi, yang terjowantahkan ke dalam nilai-nilai universal yang menjadi panutan umat manusia dunia, seperti peduli, kreatif dan pro-aktif (balligh) kejujuran dan kebenaran (shodiq), patuh dan tunduk pada janji (amanah) cerdas secara intelektual dan spiritual (fathonah), bersikap adil dan tidak tebang pilih (a’dalah), bersabar (shobar), berani mengatakan yang benar dan yang salah (syaja’ah), rendah hati dan tidak sombong (tawadhu), kasih sayang (ruhama’u), mengutamakan kepentingan umat/publik (mashlahatul ummah), dan tidak materialistic (juhud). 23 Bab 5 243 menegasikan konsep islamisasi ilmu pengetahuan. Islamisasi pengetahuan bagi Kunto cukup menyakitkan oleh karena Islam tidak dapat disamakan dengan gerakan bisnis pragmatis. Tetapi, Kunto lebih memilih pada gerakan “pengilmuan Islam”. Kedua kelemahan yang perlu disempurnakan dan peluang bagi Ahimsa-Putra, untuk mengembangkannya antara lain, karena pandangan Kunto tentang ilmu pengetahuan sosial profetik jauh dari sempurna, dan lebih merupakan model wacana parsial (comot sana comot sini). Heddy mengelaborasi pikiran Kunto, terkait dengan pembentukan konsepsi atau pandangan mengenai paradigma atau “pemikiran sistem Islam terpadu (kaffah), yang moderen dan berkeadaban. Secara langsung dengan berbagai kelebihan dan kelemahannya, Ahimsa-Putra, telah berani mengajukan suatu model pemikiran yakni I. paradigma propetik dan Islam. Rumusannya mencakup (1) basis epistimologi Islam terdiri dari Al-quran dan Sunnah, Rukun Iman, dan Rukun Islam. (2) Asumsi dasar tentang basis pengetahuan mencakup: panca indra, akal (kemampuan struktural dan simbolisasi), bahasa, wahyu atau ilham, sunnah Rasulullah, (3) asumsi dasar tentang objek material (4) asumsi dasar tentang gejala yang diteliti, (5) asumsi dasar tentang ilmu pengetahuan. (6) asumsi dasar tentang ilmu sosial/alam profetik (7) asumsi dasar tentang disiplin profetik. II. Etos Paradigma Profetik: Basis semua etos: Penghayatan, etos kerja pengabdian (untuk Allah swt, ilmu, diri sendiri, sesama dan alam semesta), etos kerja keilmuan (pengembangan unsur, pengembangan paradigma, pengembangan sistem pengetahuan), etos kerja kemanusiaan (kejujuran, ketelitian/keseksamaan, ketawadhuan), dan etos kerja kesemestaan (perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan pengembangan). Model paradigma profetik mengandung (1) struktur rukun iman dan trasformasinya (manusia pengabdian kepada Allah, ilmuwan pengabdian kepada ilmu pengetahuan), manusia persahabatan kepada Malaikat, ilmuwan kepada kolega, manusia pembacaan pada alkitab (Quraniyah) dan ilmuwan pembacaan pada kitab alamiah (qauniyah). (2) model struktur rukun Islam: Syahadat, (syahadat keilmuan, 244 Landasan Aksiologi... wahyuisme), Sholat, (sebagai perenungan dan inspirasi), Puasa (penelitian dan temuan), Zakat (Pengajaran da Penyebaran), Haji, (pertemuan dan pertemuan). Terakhir, Implikasi Epistimologi Propetik, mengandung implikasi permasalahan, implikasi konseptual, implikasi metodologi penelitian, implikasi metodologi analisis, dan implikasi representatsional (Etnografis).24 Terkait dengan paradigma profetik bagi pembentukan filsafat ilmu (epistimologi) di FH UII maka asumsi keyakinan bahwa visi rahmatan lil ‘alamien menuntut untuk diformulasikan. Pertama, paradigma profetik, dalam penjabaran ilmu hukum harus dibangun dari pandangan yang terpadu (integrated) antara nilai-nilai kebenaran (ontologis), kebenaran ilmunya (epistimologis) dan nilai-nilai manfaat (praxis). Mengakui kehadiran teori hukum alam (natural law), termasuk pandangan Thomas van Aquinas, hukum suci (lex devine) hukum alam (lex natura), hukum manusia (lex humana) sangat vital. Ilmu hukum berkeadilan memerlukan orientasi paradigma, pencerahan hukum propetik atau juga ilmu hukum berbasis religious science.25 Kedua, kepaduan ajaran ilmu hukum yang integrated berkarakter inklusif. Kesediaan proses pembelajaran ilmu hukum, yang terbuka dengan kehadiran ilmu-ilmu sosial lain di luar disiplin ilmu hukum. Kompleksitas kehidupan masyarakat yang semakin modern, menjadi sangat naif jika ilmu hukum disejajarkan dengan ilmu terapan (apllied science) yang lepas dari moralitas kebenaran dan keadilan.26 Disarikan dari tulisan Heddy Shri Ahimsa Putra, dalam dari halaman 31. Terdapat dua catatan, pertama dalam analisis paradigmatik profetik, rukun iman dan rukun Islam dijadikan landasan dalam menjelaskan berbagai hubungan antara manusia, ilmuan dalam pengbdiannya kepada Tuhan dan Ilmu. Namun, Ahimsa-Putra tampaknya, tidak memandang penting adanya Ikhsan, sebagai wilayah, yang oleh Karl Popper sebagai wilayah extra-metafisik yang juga diakomodir dalam menjustifikasi kebenaran yang diperoleh dari model ekperimentasi. 25 Belakangan ini FH UII mengembangkan pemikiran hukum profetik, dan FH Uninersitas Brawijaya mencobanya dari pendekatan Sains Religiousitas. 26 Jawahir Thontowi. 2010. Menuju Ilmu Hukum Berkeadilan. Disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar. Diselenggarakan 20 Desember di dalam Sidang Senat Terbuka Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 24 Bab 5 245 6. Simpulan Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa gagasan membangun paradigma profetik bagi pengembangan ilmu hukum tidak boleh pesimistik. Keterbukaan tersebut, tentu saja mengacu pada realitas ilmu pengetahuan, yang pada hakikatnya selalu mengalami perubahan seiring perubahan baik materiel maupun immateriel, atau faktual dan non faktual, pembaharuan melalui imitasi, adopsi dan inovasi menjadi kebutuhan bagi manusia, dala tempat, dan waktu yang berbeda. Dalam kajian sosiologi atau ilmu sosial dan filsafat secara umum, tidak dapat dihindarkan bahwa paradigma bukan saja penting tetapi diperlukan. Paradigma bukan filsafat dan bukan pula teori melainkan mengandung unsur-unsur, nilai-nilai dasar yang membentuk suatu asumsi (kepercayaan) terdiri dari teori, konsep, dan metode penelitian serta metode analisis yang digunakan sebagai cara dalam memecahkan problematika ilmu pengetahuan terhadap persoalan-persoalan realitas faktual definisi personal dan perilaku sosial sehingga dapat mewujudkan solusi yang sesuai dengan waktu dan tempat. Namun kecenderungan penggunaan paradigma ilmu sosial, psikologi, dan hubungan internasional mengarahkan model pencarian kebenaran bersumber tidak hanya pada dokumen, dan/atau teks peraturan atau sejenisnya, tetapi melakukan penelitian lapangan baik secara kuantitatif maupun kualitatif mengingat nilai prediksi pada hakikatnya salah satu unsur yang melekat atas apa yang diklaim sebagai paradigma. Karena itu, bilamana paradigma profetik dalam pengembangan filsafat ilmu, khususnya ilmu hukum akan diformulasikan tahapan yang harus dilalui sebagai berikut. Pertama, suatu cara/model dipandang sebagai paradigma profetik dalam filsafat ilmu hukum terbangun bila kelompok pemikir mensepakati landasan utama, tempat awal take off, poin of departure. Menempatkan keberadaannya (aspek ontologis) sebagai objek ilmu pengetahuan, harus bersumber pada trikotomi kebenaran 246 Landasan Aksiologi... ilmu (Ilmu Yakin), kebenaran faktual (‘ainul yaqin), dan kebenaran utuh yang mutlak (haqul yaqin). Aspek estimologis, yaitu kesepakatan menempatkan sumber kebenaran diperoleh tidak saja dari kekuatan tradisi keilmuan barat yang relatif dan bebas nilai, melainkan wajib mengakui adanya sumber wahyu, relevation, sunnah rasul yang diturunkan pada Nabi dan Rasul. Aspek aksiologis, terdapat kesepakatan bahwa seorang manusia dan ilmunya terikat dalam perilaku dan perbuatan yang bukan saja hanya menggunakan etika dan moralitas, untuk sekedar berkomunikasi dengan manusia dan lingkungan semata, tetapi juga dituntut perbaikan sebagai sikap mengabdi kepada “Tuhan Pencipta”. Tahap kedua, paradigma profetik pengembangan filsafat ilmu menuntut adanya perpaduan secara sinergis antara agama, sebagai the father or science, dan filsafat sebagai the mother agar kontradiksi internis dapat terakomodir menjadi teori-teori sosial, dan lainnya saling mendukung dalam pengujian atas dunia das sollen-das sein. Kebebasan berpikir dalam rangka innovatif yang mewujudkan sebagai diskresi (Erlyn) atau Ijtihad (Ahmad Hasan) untuk menemukan teori, model, merupakan sisa kewenangan manusia (residual power in the hand of human being), sejak setelah dalil-dalil naqli dalam kitab suci tidak ada rujukannya. Tahap ketiga, paradigma profetik dalam penyeimbangan ilmu hukum di FH UII memiliki peluang besar, meski juga bukan tanpa hambatan. Setidaknya ada tiga peluang yang dapat dijadikan basis argemen. Secara kajian Islam paradigma sebagaimana diakui Zaki Kirmani, Manhaj yang menempatkan etika/model sebagai pusat perhatian, ilmu pengetahuan barat mengakui kelemahan tersebut. Nilai Islam yang universal kemudian didialogkan dan juga memberi manfaat pada penyempurnaan model ilmu pengetahuan Barat. Kajian filsafat nasional menunjukkan dukungan atas pentingnya paradigma profetik, dan kedudukannya merupkan dasar filsafat bangsa, nilai-nilai tidak bertentangan dengan Al Qur’an dan Sunnah. Membuktikan sinergitas antara konsensi Pancasila dengan ajaran Islam, sangat tergantung pada faktor determinan apakah hukum Islam mampu membuktikan tegaknya keadilan untuk semua pihak, Islam justice for all. Bab 5 247 C. H a k i m B u t u h P r o f e t i k I n t e l e l l i g e n c e (Kecerdasan Kenabian) dalam Memutuskan Perkara di Pengadilan Oleh M. Syamsudin 1. Pendahuluan Secara formal bangsa Indonesia telah berhasil membangun dan mendirikan sebuah institusi negara merdeka yang berdasar atas konsep negara hukum. Namun cita-cita atau gagasan hukum (rechtsidee) sebagaimana yang terkandung di dalam konsep negara hukum tersebut masih mengandung banyak permasalahan dalam tahap perwujudan dan penerapannya. Kondisi negara hukum Indonesia yang tercermin dalam sistem hukumnya, masih menunjukkan keadaan yang sangat memprihatinkan. Akibatnya dunia hukum di Indonesia dewasa ini belum mampu mewujudkan sepenuhnya cita-cita dan harapan-harapan sebagaimana amanat konsep negara hukum tersebut. Di kalangan masyarakat sampai dengan dekade terakhir ini masih banyak dijumpai gejala munculnya ketidakpuasan dan bahkan ketidak percayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Terhadap keadaan yang demikian itu, telah banyak pikiran dan pendapat, baik dari kalangan para ahli hukum (teoretisi), pembuat kebijakan (legislasi) dan praktisi tentang upaya-upaya memperbaikinya. Potret perjalanan sistem hukum Indonesia masih menunjukkan adanya ketidak sinkronan antara hakikat, fungsi dan tujuan hukum yang diharapkan, baik yang tercermin dalam subtansi, struktur dan budaya hukumnya. Jika program kodifikasi dan unifikasi hukum dijadikan ukuran, maka pembangunan struktur dan subtansi hukum telah berjalan cukup baik dan stabil karena dari waktu ke waktu ada peningkatan produktivitas,27 akan tetapi pada sisi lain dapat dilihat bahwa budaya Moh. Mahfud MD. 2000. Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Yogyakarta: Gama Media. Hlm. 2-3; 27 248 Landasan Aksiologi... hukumnya cenderung merosot. Ketidak sinkronan pertumbuhan antara subtansi, struktur dan budaya hukum disebabkan adanya faktor-faktor yang tidak dan atau kurang mendukung bekerjanya sistem hukum di Indonesia.28 Dari paparan GBHN 1999, dapat diketahui bahwa Indonesia yang menganut dan mengikuti prinsip negara hukum — sebagaimana telah disebutkan dalam UUD 1945 - dalam tataran praksis 29 belum sepenuhnya dapat terwujud. Bahkan telah terjadi krisis hukum, yaitu dengan merosotnya integritas moral dan profesionalisme aparat hukum, menurunnya kesadaran hukum, buruknya mutu pelayanan, tidak adanya kepastian dan keadilan hukum. Dalam praktik hukum, ketidakpuasan masyarakat terhadap lembaga peradilan, juga selalu muncul di permukaan akhir-akhir ini. Ketidakpuasaan itu muncul terutama berkaitan dengan keputusankeputusan dari kalangan pengadilan terhadap perkara-perkara yang Baca Bab II Tap MPR No.IV/MPR/1999 tentang Kondisi Umum GBHN 1999, antara lain digambarkan sebagai berikut: “...di bidang hukum telah terjadi perkembangan yang kontroversial, di satu pihak produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum menunjukkan peningkatan. Namun, di pihak lain tidak diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat hukum, kesadaran hukum, mutu pelayanan serta tidak adanya kepastian dan keadilan hukum sehingga mengakibatkan supremasi hukum belum dapat diwujudkan.Tekad untuk memberantas segala bentuk penyelewengan sesuai tuntutan reformasi seperti korupsi, kolusi, nepotisme, serta kejahatan ekonomi keuangan dan penyalahgunaan kekuasaan belum diikuti langkahlangkah nyata dan kesungguhan pemerintah serta aparat penegak hukum dalam menerapkan dan menegakkan hukum, terjadinya campur tangan dalam proses peradilan, serta tumpang tindih dan kerancuan hukum mengakibatkan terjadinya krisis hukum. Kondisi hukum yang demikian mengakibatkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di Indonesia masih memprihatinkan yang terlihat dari berbagai pelanggaran HAM, antara lain dalam bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, dan kesewenangwenangan”; 29 Istilah praksis tidak sama dengan praktik dalam arti umum. Praksis merupakan prilaku sadar yang diyakini kebenarannya dan sarat dengan nilai-nilai yang melatarbelakanginya. Sementara pengertian praktik merupakan prilaku tanpa nilai-nilai yang dipilih secara sadar dan diyakini kebenarannya, periksa Darji Darmodiharjo & Shidarta. 1996. Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia, Jakarta : PT RajaGrafindo. Hlm., 187; 28 Bab 5 249 oleh masyarakat dianggap penting dan menarik. Ketidakpuasaan masyarakat itu juga mengakibatkan merosotnya wibawa hukum dan lembaga peradilan di Indonesia sekarang ini. Terhadap hal yang demikian telah banyak pikiran dan pendapat dari para ahli tentang bagaimana jalan memperbaikinya. Diantara banyak pikiran dan pendapat yang berkembang itu antara lain berkaitan dengan ketidakmandirian serta merosotnya martabat pribadi dari para hakim. Oleh karena itu yang harus diperbaiki adalah kemandirian serta pribadi para hakimnya.30 Hakim sebagai salah satu unsur aparat penegak hukum, di samping Polisi, Jaksa dan Pengacara/Advokat, menduduki posisi yang sangat penting dan menentukan dalam proses pemeriksaan perkara dalam proses peradilan. Setiap proses pemeriksaan perkara di pengadilan, baik berupa perkara perdata, pidana, maupun tata usaha negara pada akhirnya berujung dan ditentukan oleh keputusan hakim sebagai produk akhir proses beracara di pengadilan. Oleh karena itu penting dilakukan kajian tentang dinamika hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan. Begitu berat sebenarnya tugas seorang hakim, karena di tangan hakimlah pencari keadilan akan meletakkan kepercayaann dan harapannya. Hakim bukanlah malaikat yang dapat melakonkan hukum seperti simbol dewi keadilan yang membawa pedang sambil matanya ditutup, di mana hukum diterapkan dengan prinsip-prinsip mesin secara akurat, konsisten tanpa melihat orangnya. Hakim tetaplah seorang manusia, yang akan memunculkan segi kemanusiaannya jika berhadapan dengan manusia lain di dalam ruang sidang. Oleh karena itu selain muatan hukum dalam proses persidangan, hakim juga diliputi oleh muatan psikologis dalam menerapkan hukum. Oleh karena itu aspek psikologis di bidang hukum amat besar, karena hukum melibatkan manusia sebagai pelaku-pelaku hukum.31 Selama pengambilan keputusan belum dilakukan dengan peralatan mekanik, selama itu pula faktor manusia, yaitu hakim masih Varia Peradilan. 1996. Hlm. 126 Yusti Probowati R. “Putusan Hakim Pada Perkara Pidana: Kajian Psikologis”. Buletin Psikologi Fakultas Psikologi UGM tahun III Nomor 1 Agustus 1995. Hlm.1; 30 31 250 Landasan Aksiologi... perlu dipelajari dalam berbagi seluk beluknya. Sebagai manusia biasa, hakim tidak akan lepas dari kesalahan yang berasal dari kelemahan yang dimilikinya. Meskipun peraturan yang megatur keputusan pengadilan telah ditetapkan, tidak berarti bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak terpengaruh oleh faktor-faktor non-hukum. Terhadap keputusan hakim tersebut, orang (para pihak) yang terkait dengan keputusan tersebut boleh merasa puas atau tidak puas, adil atau tidak adil. Keputusan hakim yang dianggap tidak memberikan rasa keadilan pada peradilan tingkat pertama, orang (para pihak) yang terkait dengan keputusan itu masih diberikan kesempatan untuk mengajukan banding atau kasasi. 2. F a k t o r - f a k t o r Non-Legal yang Ikut Mempengaruhi Hakim dalam Memutuskan Perkara Dalam kaitan dengan prinsip kebebasan peradilan dan kebebasan hakim, Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa, hakim itu bebas dalam atau untuk mengadili sesuai dengan hati nuraninya/ keyakinannya tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Hakim bebas memeriksa, membuktikan dan memutuskan perkara berdasarkan hati nuraninya. Di samping itu juga bebas dari campur tangan pihak ekstra yudisial.32 Lebih lanjut dikatakan bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam UUD. Tetapi di dalam praktik ketentuan itu tidak jarang dilanggar, antara lain dengan mengambil jalan pintas dengan menggunakan surat sakti, tilpon sakti, suap dan sebagainya.33 Hoentink mengatakan bahwa, hakim tidak boleh mengadili melulu menurut perasaan keadilan diri-pribadinya, melainkan ia terikat kepada nilai-nilai yang berlaku secara objektif di dalam masyarakat. Scholten Sudikno Mertokusumo. 1997. “Sistem Peradilan di Indonesia”. Jurnal Hukum FHUII. No.9. Vol.4-1997. Hlm. 5; 33 Ibid. 32 Bab 5 251 mengatakan bahwa, hakim terikat kepada sistem hukum yang telah terbentuk dan yang berkembang di dalam masyarakat. Dengan tiaptiap putusannya hakim menyatakan dan memperkuat kehidupan normanorma hukum yang tidak tertulis.34 Apabila hakim sudah merasa cukup dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya, maka tibalah saatnya ia akan memberikan putusan atas perkara yang diajukan. Dalam memutus perkara tersebut disyaratkan dalam undang-undang bahwa di samping berdasarkan alatalat bukti yang sudah ditentukan oleh undang-undang, juga harus berdasarkan pada ‘keyakinan hakim’. Untuk menentukan adanya keyakinan ini tidaklah mudah bagi hakim dalam menjalankan tugas profesinya. Keadaan demikian dikhawatirkan jika hakim salah dalam menentukan keyakinanya, maka akan terjadi kesesatan yang berakibat putusan hakim tidak adil. Menurut Mulyatno, keyakinan hakim adalah suatu keyakinan yang ada pada diri hakim, kalau ia sudah tidak menyangsikan sama sekali akan adanya kemungkinan lain daripada yang digambarkan kepadanya melalui suatu pembuktian. Jadi hal yang diyakini kebenarannya itu sudah di luar keragu-raguan yang masuk akal (beyond reasonable doubt).35 Peraturan hukum menggariskan bahwa hakim tidak boleh menilai hal-hal lain kecuali faktor yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Namun dalam kenyataan menurut penelitian yang pernah dilakukan, proses putusan hakim, seringkali terpengaruh oleh faktor-faktor nonhukum, seperti: (1) sifat kepribadian hakim, yaitu bahwa hakim yang bersifat otoriter akan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hakim yang tidak bersifat otoriter. (2) faktor penampilan terdakwa, yaitu bahwa penampilan terdakwa di ruang sidang, seperti gaya bicara, postur ketika duduk dan berdiri, cara berpakaian akan ikut berpengaruh pada putusan hakim yang dijatuhkan. (3) faktor diri si korban, yaitu bahwa I.G.N. Soegangga. 1994. Pengantar Hukum Adat. Semarang: Badan Penerbit Undip. Hlm. 52; 35 Mulyatno. 1982. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yogyakarta : Bina Aksara. Hlm.21 34 252 Landasan Aksiologi... bila si korban yang rupanya menarik, akan lebih besar kemungkinan si terdakwa untuk mendapatkan hukuman bersalah dan dihukum lebih berat. Faktor usia, tingkat pendidikan dan status sosial ekonomi korban ikut berpengaruh pula terhadap berat ringannya hukuman bagi si terdakwa.36 Penelitian lain juga menunjukkan bahwa faktor-faktor yang ikut mempengaruhi keputusan hakim antara lain adalah: (1) faktor internal, yang terdiri atas: faktor peraturan perundang-undangan, faktor kedudukan hakim sebagai PNS, faktor organisatoris, faktor sarana dan prasarana dan SDM. (2) faktor ekternal, yang terdiri atas faktor kekuasaan, faktor opini publik dan pemberitaan pers, serta faktor kepentingan tertentu.37 Faktor undang-undang yang mempengaruhi hakim dalam memutus perkara terjadi ketika hakim berhadapan dengan undang-undang yang berkaitan dengan makna, isi dan spirit yang terkandung dalam kaidahkaidah hukum. Meskipun dalam kacamata normatif rumusan hukum (undang-undang) sudah cukup jelas, namun secara sosiologis ternyata tidak mudah bagi aparat (hakim) untuk menangkap makna, isi dan spirit dari peraturan tersebut. Dengan kata lain, undang-undang itu tidak siap pakai. Oleh karena itu masih diperlukan interpretasi terhadap kaidah-kaidah hukum tersebut. Setiap penegak hukum (hakim) akan berupaya mencari kandungan isi peraturan dengan cara menafsirkan peraturan tersebut. Dalam proses penafsiran ini, tidak semua aparat (termasuk hakim) mampu memahami peraruran perundangan secara tepat. Kelemahan dalam memahami isi dan spirit undang-undang merupakan cacat yuridis pertama dalam mengaplikasikan peraturan.38 Faktor kedudukan hakim juga sangat mempengaruhi hakim dalam putusannya. Meskipun secara formal hakim memiliki kebebasan dalam M. Syamsudin. 1999. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Hakim dalam Memutus Perkara di Pengadilan”. Jurnal Arena Almamater N0.51 Tahun XIV JANUARI-MARET 1999. Hlm. 10 37 Ibid. 38 Salman Luthan, & Agus Triyanta. 1997. “Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparat Keadilan”. Jurnal Hukum FH-UII. No.9. Vol.4-1997. Hlm. 60. 36 Bab 5 253 menengani suatu perkara namun sangat mungkin terjadi bahwa kedudukannya sebagai pegawai negeri sipil secara psikologis menyebabkan hakim tidak berani mengambil sikap atau membuat keputusan-keputusan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang merupakan induk korpsnya. Kekawatiran akan terhambatnya karir atau dimutasikan ke daerah-daerah kering dapat juga mempengaruhi hakim dalam menangani suatu perkara, apalagi jika perkara itu menyangkut kepentingan instansi pemerintahan atau oknum pejabat atau keluarganya. Dengan peletakan kedudukan hakim sebagai eksekutif maka secara organisatoris lebih mudah terjadi intervensi atas kebebasan hakim oleh kekuatan dari luar. Ini sesuai dengan watak korps dan birokrasi yang pada umumnya mempunyai ikatan-ikatan tertentu bagi anggota-anggotanya. Dalam keadaan demikian maka sulit diharapkan sikap netral dan independen seorang hakim dalam menengani perkaraperkara, terutama yang berakitan dengan masalah politik. Dalam kenyataan perkara-perkara politik yang masuk ke pengadilan pihak pemerintah yang selalu menang.39 Faktor nilai budaya yang diduga mempengaruhi hakim dalam memutuskan perkara adalah nilai budaya paternalistik. Nilai budaya ini berorientasi kepada atasan dalam suatu organisasi. Karena budaya paternalistik ini dapat saja mempengaruhi hakim merasa tidak enak, ewuh pekewuh, jika harus memutus oknum pejabat pemerintah yang notabene merupakan atasannya. Budaya paternalistik atau patrimonial yang berkembang di Indonesia menyebabkan tampilnya pilihan sikap dari seorang pegawai negeri untuk tidak melawan kehendak atasannya, sehingga hakim akan sulit bersikap netral dan independen dalam perkara-perkara yang melibatkan pemerintah sebagai salah satu pihak. Dalam budaya paternalistik terkandung paham bapakisme yang meletakkan bapak (pemerintah) sebagai tumpuhan dan sumber pemenuhan kebutuhan materiil serta emosionil antara bapak dengan Moh.Mahfud,MD. 1997. “Politik Hukum untuk Independensi Lembaga Peradilan”. Jurnal Hukum FH-UII. No.9.Vol.4-1997. Hlm 31. 39 Landasan Aksiologi... 254 anak (clan) dan anak dijadikan tulang punggung yang setia kepada bapak, membantu terselenggaranya upacara-upacara keluarga, dan bahkan bersedia mempertaruhkan jiwa demi kepentingan bapak yang harus dihormati, ditaati dan pantang ditentang.40 Faktor moral dan kepribadian hakim juga diduga mempengaruhi hakim dalam memutus perkara. Adanya isu-isu mafia peradilan, kolusi, suap dan sebagainya sebagai indikator bahwa moral-kepribadian hakim sangat menentukan dan berpengaruh. Moralitas adalah kesesuaian sikap dan perbuatan dengan norma atau hukum batiniah yang dianggap sebagai kewajiban. Moralitas akan tercapai apabila menaati hukum lahiriah, bukan lantaran hal itu membawa akibat yang menguntungkan atau lantaran takut pada penguasa penegak hukum. Tetapi hal itu merupakan kesadaran batin bahwa menaati hukum itu merupakan suatu kewajiban. Moral adalah hasil penilaian tentang baik-buruk seseorang atau suatu masyarakat. Penelaian berarti tindakan memberi nilai, meletakkan kualitas tertentu terhadap seseorang atau masyarakat. Adapun yang dinilai adalah keseluruhan pribadi orang (hakim) atau masyarakat, bukan hanya aspek-aspek tertentu saja dari orang atau masyarakat itu. Oleh karena itu moral berkaitan dengan integritas, harkat dan martabat manusia. Sifat kepribadian hakim berpengaruh pula pada keputusan hakim. Hakim yang bersifat otoriter akan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hakim yang tidak bersifat otoriter. Penelitian di luar negeri yang dilakukan oleh Mitchell dan Byrne ( dalam Brigham, 1991) menemukan bahwa juri dengan kepribadian otoriter akan sering menyatakan terdakwa bersalah, sedangkan Mills & Bohannon (dalam Brigham, 1991) menemukan bahwa juri yang memilki empati tinggi cenderung untuk memutuskan terdakwa tidak bersalah. Faktor psikologis lain yang juga mempengaruhi hakim itu antara lain: daya tarik sosial, daya tarik fisik dan daya tarik sikap. Banyak penyelidikan yang memfokuskan pada daya tarik sosial ini sebagai salah satu faktor yang tidak dapat diabaikan. Terdakwa yang tidak memiliki 40 Ibid. Hlm. 30. Bab 5 255 daya tarik secara sosial dijatuhi hukuman lebih berat baik pada tahap pra peradilan maupun peradilan tingkat akhir (Berg & Vidmar; Kulka & Kessler; Solomon & Schopler, dalam Bartol & Bartol, 1994). Berkenaan dengan gender pada masa kini tampaknya sudah lebih adil. Diskriminasi ras juga berpengaruh, namun ini lebih kecil dibandingkan dengan status sosial ekonomi (Bartol & Bartol, 1994). Berdasarkan penelitian dalam bidang Psikologi Sosial, sebagian besar orang meyakini bahwa orang yang memiliki daya tarik fisik cenderung disukai secara sosial (social desirable) dibandingkan dengan orang yang tidak menarik (Dion, Berscheid & Walster dalam Bartol& Bartol, 1994). Toleransi terhadap pelanggaran hukum/kekerasan lebih besar manakala itu dilakukan oleh orang yang menarik secara fisik. Menarik tentu saja merupakan kriteria subjektif yang dapat dihubungkan dengan bermacam-macam variabel latar belakang seperti: keadaan sosial ekonomi, terjaminnya kesehatan dan gizi. Stewart (Bartol & Bartol, 1994) melaporkan bahwa terdakwa yang fisiknya kurang menarik akan diberikan hukuman lebih berat. Hasil penelitian Victoria Esses & Christopher Webster pada bangsa Canada (Bartol & Bartol, 1994) membuktikan bahwa daya tarik fisik mempengaruhi keputusan peradilan untuk menempatkan orang yang bersalah pada klasifikasi khusus yang disebut “Kategori Orang Berbahaya” (Sebutan pada kode kriminal Canada). Hakim meyakini bahwa narapidana yang bertampang tidak menarik, tidak dapat menahan diri untuk melakukan kejahatan lagi setelah dibebaskan. Di ruang persidangan akan terjadi ketegangan yang bersumber dari selisih paham atau ketidaksamaan sikap antara terdakwa dengan yang mengadilinya. Selisih paham tersebut dapat membentuk penilaian tertentu pada diri terdakwa. Penilaian yang positif akan timbul kalau orang tersebut memiliki sikap yang sama, demikian menurut pandangan teori penguat daya tarik (reinforcement theory of attractiveness). Vonis bersalah mudah dijatuhkan pada terdakwa yang lebih sering berselisih paham (Mitchell & Byrne dalam Bartol & Bartol, 1994). 256 Landasan Aksiologi... Byrne (Bartol & Bartol, 1994) memprediksi bahwa persepsi yang sama merupakan penguat sedangkan persepsi yang tidak sama adalah sebaliknya bahkan mungkin menghasilkan respon menghukum. Kesamaan berperan penting untuk memunculkan rasa suka karena dapat memberikan petunjuk mengenai kebenaran interpretasinya sendiri pada realitas sosial. Studi lanjutan mengenai teori ini mencoba menghubungkan antara kesamaan sikap pemberi putusan peradilan (dalam sistem peradilan Amerika dilakukan oleh Juri) dan terdakwa, karakter otoriter serta hubungan antara keduanya tersebut dengan vonis bersalah. Kepribadian pemberi putusan peradilan ternyata berperan cukup besar. Kepribadian sangat otoriter terpengaruh secara signifikan dengan sikap yang sama dari terdakwa. Selain berkenaan dengan persepsi, aspek lain dari sikap yang dapat berpengaruh adalah gaya bicara, gerak dan postur tubuh. Pada saat terdakwa menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum, orang-orang dalam ruang sidang peradilan akan mendengarkan bahasa verbal yang disampaikan ketika berargumentasi maupun bahasa non verbal yang tampak dari gelagat, gerak atau postur tubuhnya. Gaya bicara yang persuasif penuh percaya diri (suara berat, mantap), gerak dan postur tubuh yang sesuai (ekspresif tetapi tetap tenang, tidak banyak melakukan gerakan yang mencerminkan kegelisahan) dikaitkan dengan pernyataan yang dapat dipercaya, tidak meragukan, tidak membosankan sehingga “pendengar’ tampak mendengarkan dengan seksama (Maslow, Yoselson & London dalam Bartol & Bartol, 1994). Jadi dapat dikatakan bahwa respon orang setelah melakukan pengamatan orang lain adalah sesuai dengan hal yang ditampilkan oleh orang tersebut. Menurut Jones & Davis (Sarwono, 1995) respon tersebut adalah hasil dari kesimpulan yang dapat ditarik atas perilaku tertentu yang kemudian dibuat peramalan terhadap niat dari orang lain tersebut (inferensi korespondensi). Berdasarkan proses kognisi seorang hakim dalam mengambil putusan, maka proses kognitif pengumpulan informasi terdiri dari 3 Bab 5 257 (tiga) tahapan yaitu: perhatian, encoding dan retrieval. Pemrosesan informasi dalam diri manusia (hakim) ini sering mengalami bias. Skema adalah istilah yang dikembangkan oleh ahli psikologi sosial untuk menggambarkan bagaimana informasi sosial secara selektif diterima dan diorganisasi dalam ingatan. Ada 4 (empat) macam skema yaitu: (1) self scheme yaitu persepsi/evaluasi terhadap diri sendiri; (2) Person scheme yang berisikan asumsi seseorang tentang orang tertentu; (3) Role scheme yang berisikan konsep-konsep tentang norma atau perilaku yang sesuai bagi orang dalam berbagai kategori sosial, misal role sebagai TNI; (4) Event scheme yang berisikan pengetahuan tentang suatu kejadian sosial. Skema ini akan banyak memberi pengaruh dalam proses informasi sosial (Brigham, 1991). Pada tahap proses perhatian, skema akan mempengaruhi persepsi seseorang terhadap objek perhatian. Seorang kyai misalnya akan dipersepsi sebagai orang baik, karena adanya role schema, dan jika seorang kyai melakukan kejahatan akan menyebabkan adanya ketidaksesuaian dengan role scheme dalam diri hakim sehingga pantas dihukum yang lebih berat dibanding seorang anggota masyarakat biasa. Dalam tahap encoding (penyimpanan) informasi dapat dilakukan dalam short term memory dan long term memory. Skema juga memainkan peranan penting dalam menentukan informasi mana yang akan diencoding. Tulving dan Thomson (dalam Smith, 1991) mengatakan bahwa, informasi akan disimpan dalam ingatan jika informasi tersebut konsisten dengan struktur pengetahuan (skema) yang ada. Hal ini sering menyebabkan terjadinya contrast effect, yaitu tendensi untuk menyuport skema yang merupakan harapan walaupun skema tersebut bertentangan dengan realita. Seorang hakim yang memiliki person scheme bahwa wanita yang cantik dan lembut tidak mungkin melakukan perbuatan negatif, akan tetap mempertahankan skema tersebut ketika menghadapai terdakwa seperti itu dan memberi vonios hukuman yang lebih ringan walau kejahatan yang dilakukan tergolong berat. Dalam tahap retrieval (mengingat kembali), skema juga berpengaruh sehingga sering terjadi priming effect, yaitu skema yang 258 Landasan Aksiologi... sering digunakan akan lebih peka untuk digunakan kembali. Misal seorang hakim yang sering berhadapan dengan penjahat yang bentuk tubuhnya besar dan penuh tato, maka ketika mengadili terdakwa dengan tato dan tubuh besar akan beranggapan bahwa terdakwa pasti melakukan kejahatan. Lebih jauh lagi akan terjadi confirmatory bias, yaitu kecenderungan untuk mencari bukti-bukti yang mendukung anggapan ini. 3. Arti Penting Profetik Intelligence bagi Hakim Dari tinjauan teoretis di atas dapat diketahui bahwa dalam realitanya banyak faktor non-legal yang ikut berperan dalam proses pembuatan putusan hukum oleh hakim. Hakim tidaklah sekedar mejalankan prosedur dan kemudian menerapkan pasal-pasal dalam undang-undang yang cocok atas kejadian atau peristiwa yang akan dihukumkan, akan tetapi secara sosiologis (faktual) banyak variabel sosial yang ikut andil. Memang dalam proses penegakan hukum prosedur dan pasal-pasal dalam undang-undang itu tidak boleh diabaikan, karena itu merupakan sarana/perlengkapan pokoknya. Akan tetapi harus dingat bahwa sarana dan perlengkapan itu bukanlah tujuan yang sesungguhnya ingin dicapai oleh hukum. Prosedur dan pasal-pasal itu hanyalah sarana dan perlengkapan yang diharapkan dapat mengantarkan para penegak hukum untuk sampai pada tujuan hukum yang sesungguhnya. Itulah sebabnya kenapa sarana/perlengkapan itu harus dibuat jelas, sistematis, transparan, terkontrol dan logis dengan maksud agar dapat memberikan kepastian bagi para pencari keadilan hukum. Dengan berpikir yang demikian itu, maka menegakkan hukum itu pada hakikatnya terkait dengan masalah-masalah mendasar seperti keadilan, kepastian dan kemanfaatan sosial. Radbruch (1961) menyebut tiga hal itu sebagai nilai-nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Menegakkan hukum merupakan suatu upaya untuk mewujudkan nilainilai tersebut menjadi kenyataan.41 Sekali lagi prosedur dan aturan Satjipto Rahardjo. Tanpa tahun. Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Bandung : Sinar Baru. Hlm. 15. 41 Bab 5 259 hukum itu bukanlah tujuan hukum, tetapi sarana/perlengakapan yang fungsinya mengantarkan para penegak hukum untuk sampai pada tujuan hukum agar mewujud menjadi kenyataan, yaitu keadilan, kepastian dan kemaslahatan. Menyadari akan hal tersebut maka pekerjaan menegakkan hukum tentunya bukanlah pekerjaan yang mudah dan sederhana, seperti halnya menghidupkan tombol mesin, jika tombolnya dipencet lantas semua komponen-komponen yang ada bekerja secara otomatis. Pekerjaan ini membutuhkan energi yang cukup banyak dan dituntut kerja keras dan sungguh-sungguh karena terkait dengan ‘nasib manusia’ yang dikenai hukum. Di sisi lain, terkait pula dengan ‘nasib masyarakat’ secara luas jika berhubungan dengan kepentingan-kepentingan di bidang hukum publik, seperti kejahatan, kesusilaan, pelanggaran HAM, dsb. Kerja keras dan sungguh-sungguh ini dalam bahasa Agama (Islam) dikategorikan sebagai ‘jihad’. Pendek kata pekerjaan menegakkan hukum mempunyai watak tersendiri. Penulis mempunyai pikiran bahwa keterpurukan penegakan hukum di Indonesia antara lain lebih disebabkan karena belum terwujudnya nilai-nilai dasar hukum tersebut dalam kenyataan, sehingga tujuan hakiki dari hukum itupun masih jauh dari harapan. Para penegak hukum belum menjalankan fungsinya secara tepat dan optimal untuk mewujudkan tujuan hukum tersebut. Fungsi penegakan hukum yang semestinya diarahkan untuk mencapai tujuan hukum dalam proses perjalanannya mengalami distorsi, disfungsi atau bahkan mal-fungsi yang dilakukan oleh penegak hukum sendiri, baik dari unsur hakim, panitera, pengacara, polisi, jaksa dan para broker perkara. Keadaan ini digambarkan sebagai Mafioso Peradilan. Gerakan kelompok mafioso ini bersifat sistemik, yaitu dari pengadilan tingkat pertama, banding, dan Mahkamah Agung. Modus operandinya sangat bervariatif mulai dari SMS, telepon, pertemuan di susdut-sudut pengadilan, café, mengundang sebagai pembicara, dsb.42 42 Busjro Muqodas. 2006. “Peran Komisi Yudisial RI dalam pemberantasan Mafia 260 Landasan Aksiologi... Keterpurukan penegakan hukum yang digambarkan di atas pada puncaknya bangsa kita telah terjatuh pada keadaan krisis hukum. Krisis adalah keadaan tidak normal oleh karena berbagai institusi yang telah dinormakan untuk menata proses-proses dalam masyarakat tidak mampu lagi menjalankan fungsinya secara tepat. Hukum kehilangan kepercayaan dan pamor untuk mewujudkan nilai keadilan yang harus diberikan. Ia tidak lagi berada pada posisi otoritatif untuk menata dan mengendalikan proses-proses ekonomi, sosial, politik dsb, melainkan difungsikan sebagai alat untuk kepentingan kekuasaan. Hukum tidak lagi bekerja secara otentik. Dampak dari ketidakpercayaan pada penegakan hukum tersebut, sebagian rakyat kemudian melakukan tindakan penyelesaian sendiri, yang salah satu bentuknya adalah perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting). Situasi sosial menjadi anomis dan setiap orang bebas membuat tafsiran, melakukan dan memutuskan tindakan sendiri. Satjipto Rahardjo menggambarkan sistuasi ini sebagai Era Hukum Rakyat.43 Dalam situasi krisis atau tidak normal ini dibutuhkan pula caracara penyelesaian hukum yang tidak normal atau cara yang di luar kebiasaan (extra-ordinary) akan tetapi masih dalam koridor / kerangka dari tujuan hukum tersebut. Cara yang luar biasa ini bukan berarti bertindak anarkis, akan tetapi berwatak progresif. Berpikir luar biasa pada intinya adalah tidak membaca undang-undang seperti orang mengeja sebuah teks, akan tetapi mencari dan mengungkap makna dari undang-undang tersebut. Akibat mencari makna itu, lalu kita bisa dan berani bertindak rule-breaking. Berpikir luar biasa ini harus dimulai dari kalangan komunitas hukum seperti hakim, jaksa, advokat, polisi dan akademisi.44 peradilan di Indonesia”. Makalah dalam Diskusi Publik Komisi Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Jawa Tengah, 1 Pebruari 2006. Hlm. 2; 43 Satjipto Rahardjo dalam harian Kompas. 44 Satjipto Rahardjo. 2006. “Pemberantasan Korupsi Progresif ”. Makalah disampaikan Pada diskusi Peran Komisi Yudisial dalam Pemberantasan Mafia Peradilan di Indonesia. FH Unissula / Kp2KKN Semarang 1 pebruat\ri, 2006. Hlm.1-2. Bab 5 261 Rule-breaking membutuhkan berbagai pendekatan cara penyelesaian hukum yang holistik dan bahkan ekstra legal untuk menggali makna hukum. Pengalaman penyelesaian hukum yang hanya mengandalkan pendekatan yuridis-formal yang bersifat linier hanya menambah deretan kekecewaan para pencari keadilan. Sudah saatnya para akademisi dan praktisi hukum berani mentransformasikan diri untuk mencari pendekatan dan cara berpikir alternatif untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang kian rumit dan kompleks. Berbagai pendekatan yang ada bukan saatnya lagi dipertentangkan dan dipersalahkan, akan tetapi justru saling melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada dengan kelebihan masing-masing. Para lawyer harus bersikap terbuka dengan perkembangan yang terjadi dan tak perlu menutup diri. Bukankah ilmu pengetahuan itu dinamis dan tak pernah berhenti dengan inovasi-inovasi.45 Profetik Intelligence (PI) adalah sebuah tawaran pendekatan alternatif dalam rangka ikut mengisi rule-breaking tersebut. PI dibutuhkan bagi para penegak hukum untuk memperluas dan sekaligus mengasah kepekaan nurani dan spiritualnya. Bukankah para penegak hukum itu juga dituntut dalam profesinya untuk mengejawantahkan doktrin dalam setiap keputusan akhir dari proses penegakan hukum, yang berbunyi: ‘Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Doktrin ini menuntut para penegak hukum untuk mengembangkan dan sekaligus membekali dirinya dengan PI. Konsep tentang kecerdasan kenabian ini merupakan konsep yang diambil dari psikologi untuk mengukur tingkat kematangan kepribadian seseorang. Konsep ini bermanfaat untuk pengembangan kepribadian seseorang terutama yang berkecimpung dalam uapaya-upaya penyelesaian masalah-masalah kemanusiaan. PI merupakan pendekatan holistik di dunia psikologi yang menyatukan pendekatan-pendekatan yang ada sebelumnya yaitu: Cognitive Intelligence, Emotional Intelligence, Satjipto Rahardjo, “Ilmu Hukum dan Garis Depan Sains”. Makalah Bacaan Bagi Mahasiswa program Doktor Hukum Undip Untuk Matakuliah Ilmu Hukum dan teori Hukum. 45 262 Landasan Aksiologi... Adversity Intelligence, dan Spiritual Intelligence. Penegakan hukum membutuhkan PI untuk mengatasi krisis hukum yang terjadi terutama terkait dengan merosotnya moralitas penegak hukum yang selalu menjadi sorotan publik akhir-akhir ini. Konsep PI ini pernah dibahas dalam International Conference on Moslems and Islam in the 21nd Century: Image and Reality di Malaysia pada tanggal 4-6 Agustus 2004. Konsep ini ternyata mendapat sambutan yang hangat dalam forum ilmiah tersebut. Padahal di Indonesia, konsep tentang kecerdasan kenabian ini masih belum banyak dimengerti dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di dunia hukum. Kecerdasan kenabian adalah kemampuan seseorang untuk mentrasformasikan diri berinteraksi, bersosialisasi, beradaptasi dengan lingkungan vertikal dan horisontal serta dapat memahami, mengambil manfaat, hikmah dari kehidupan langit dan bumi, jasmani dan ruhani, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Kecerdasan kenabian akan diperoleh jika nurani mampu melakukan fungsi koordinasi dan pembimbingan.46 Pada hakikatnya setiap orang dapat mencapai kecerdasan kenabian, asal orang tersebut mau melakukan proses transformasi diri. Proses ini dimaksudkan untuk mengasah hati nurani agar bersih dari bekasanbekasan noda akibat dosa-dosa yang telah dilakukan seperti halnya membersihkan kaca yang telah tertutupi oleh debu yang melekat bertahun-tahun lamanya. Transformasi diri mencakup penyadaran diri, penemuan diri dan pengembangan diri dengan menghayatai dan mengamalkan sifat-sifat kenabian seperti sidiq (prinsip kejujuran), amanah (dapat dipercaya), tabligh (terbuka) dan fatonah (cerdas). 4. Simpulan Profetik Intelligence dibutuhkan bagi hakim dan juga para penegak hukum yang lain untuk memperluas dan sekaligus mengasah kecerdasan nurani dan spiritualnya. Penegakan hukum membutuhkan Hamdani Bakran. 2005. Prophetic Intelligence, Kecerdasan Kenabian. Yogyakarta: Islamika. Hlm. 38. 46 Bab 5 263 Profetik Intelligence untuk mengatasi krisis hukum yang terjadi terutama terkait dengan merosotnya moralitas penegak hukum yang selalu menjadi sorotan publik akhir-akhir ini. Dasar pentingnya Profetik Intelligence bagi hakim adalah doktrin dalam setiap pembuatan keputusan hukum yang selalu diawali dengan irah-irah: ‘Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Doktrin ini menuntut para penegak hukum untuk mengembangkan dan sekaligus membekali dirinya dengan Profetik Intelligence. Konsep tentang kecerdasan kenabian ini merupakan konsep yang diambil dari psikologi untuk mengukur tingkat kematangan kepribadian seseorang. Konsep ini bermanfaat untuk pengembangan kepribadian seseorang terutama yang berkecimpung dalam uapaya-upaya penyelesaian masalahmasalah kemanusiaan. Profetik Intelligence merupakan pendekatan holistik di dunia psikologi yang menyatukan pendekatan-pendekatan yang ada sebelumnya yaitu: Cognitive Intelligence, Emotional Intelligence, Adversity Intelligence, dan Spiritual Intelligence. D. Hakim dan Penegakan Keadilan Profetik dalam Peradilan Oleh Bambang Sutiyoso 1. Pendahuluan Dalam berbagai penanganan kasus hukum yang terjadi di tanah air, seringkali mencuat menjadi bahan perbincangan publik karena putusan peradilan dianggap mengabaikan nilai-nilai keadilan yang semestinya dirasakan oleh masyarakat dan pencari keadilan. Proses hukum di lingkungan peradilan Indonesia hingga saat ini dianggap belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya. Keadilan seolah menjadi ‘barang mahal’ yang jauh dari jangkauan masyarakat. Beberapa kasus yang sempat melukai rasa keadilan masyarakat di antaranya kasus penempatan Ayin (Artalyta Suryani) di ruang khusus 264 Landasan Aksiologi... yang cukup mewah di Rutan Pondok Bambu beberapa waktu lalu dan kelambanan penanganan kasus Anggodo merupakan secuil dari wajah buram penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Belum lagi kasus Prita Mulyasari yang dianggap menghina pihak Rumah Sakit Omni International, pencurian buah semangka, randu, tanaman jagung, ataupun pencurian biji kakao oleh Nenek Minah, semakin menambah daftar panjang potret buram dalam praktik penegakan hukum di negeri ini. Penegakan hukum yang berjalan selama ini terkesan kuat masih berorientasi dalam bentuk keadilan prosedural yang sangat menekankan pada aspek regularitas dan penerapan formalitas legal semata. Sejalan dengan itu rekayasa hukum menjadi fenomena yang cukup kuat dalam hampir setiap penegakan hukum di negeri ini. Keadilan substantif sebagai sumber keadilan prosedural masih bersifat konsep parsial dan belum menjangkau seutuhnya ide-ide dan realitas yang seharusnya menjadi bagian intrinsik dari konsep dan penegakan keadilan.47 Akibatnya, penegakan hukum menjadi kurang atau bahkan tidak mampu menyelesaikan inti persoalan sebenarnya. Suara orang atau masyarakat yang tertindas sebagai subjek yang sangat memerlukan keadilan hampir terabaikan sama sekali. Orang yang selama ini mengalami ketidakadilan, atau bahkan masyarakat secara keseluruhan kian jauh dari sentuhan dan rasa keadilan. Bahkan, sering terjadi, atas nama keadilan, para pencari keadilan menjadi korban penegakan hukum formal. Realitas ini menjadikan penegakan keadilan berwajah ambivalen yang jauh dari nilai-nilai keadilan hakiki dan terkadang justru menyodok rasa keadilan itu sendiri.48 Tidak mengherankan dalam praktik penegakan hukum yang terjadi acap kali dijumpai ketidakpuasan dan kekecewaan masyarakat dan para pencari keadilan terhadap kinerja peradilan yang dianggap tidak objektif, Abdul Ala, Pembumian Keadilan Substantif, dalam http://www.sunanampel.ac.id/publicactivity/detail.php?id=28, diakses tanggal 20 April 2010. 48 Ibid. 47 Bab 5 265 kurang menjaga integritas, dan bahkan kurang professional. Produk peradilan yang berupa putusan hakim sering dianggap kontroversi, cenderung tidak dapat diterima oleh kalangan luas hukum serta tidak sejalan dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.49 Dengan kata lain, putusan-putusan yang dijatuhkan dianggap tidak berdasarkan pada pertimbangan hukum yang cermat dan komprehensif (Onvoeldoende gemotiverd), tetapi hanya didasarkan pada silogisme yang dangkal dalam mengkualifikasi peristiwa hukumnya yang kemudian berdampak pula pada konstitusi hukumnya. Salah satu penyebabnya adalah adanya korupsi peradilan (judicial corruption), yang lebih populer disebut dengan mafia peradilan, yaitu adanya konspirasi dan penyalahgunaan wewenang di antara aparat keadilan untuk mempermainkan hukum demi keuntungan pribadi.50 Banyaknya intervensi dan tekanan pihak luar terhadap hakim, terkadang membuat kinerja hakim tidak lagi optimal, atau bahkan memilih bersikap opportunis. Tidak semua hakim dapat mengatakan yang benar adalah benar, dan yang salah adalah salah. Belum lagi munculnya “makelar kasus”yang menghalalkan segala cara seperti jual beli perkara, semakin menambah coreng moreng dunia peradilan. Dalam konteks itulah, dalam tulisan ini berupaya mengkaji beberapa persoalan terkait dengan tugas Hakim dalam peradilan, beberapa konsep keadilan dan format ideal keadilan putusan dan sejauhmana keadilan profetik diterapkan dalam praktik peradilan. Paparan tulisan ini ini diharapkan dapat membuka ruang diskusi lebih jauh tentang gagasan penegakan keadilan profetik dalam peradilan Indonesia yang menjadi wacana pilihan yang dikehendaki oleh masyarakat dan pencari keadilan. Bambang Sutiyoso. 2009. Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan, Jogjakarta, UII Press. Hlm. 6. 50 Danang Widoyoko, et. al. 2002. Menyingkap Tabir Mafia Peradilan, Jakarta, ICW. Hlm. 24. 49 266 Landasan Aksiologi... 2. Tugas dan Kewajiban Hakim Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut, hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan. Setelah memahami tugas dan kewajibannya, selanjutnya hakim harus berupaya secara profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya. Dalam Pasal 1 butir (5,7) UU No. 48 Tahun 2009 di kemukakan tentang ruang lingkup Hakim, yaitu hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut, serta hakim pada Mahkamah Konstitusi. Hakikatnya tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Meskipun demikian tugas dan kewajiban hakim dapat diperinci lebih lanjut, yang dalam hal ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu tugas hakim secara normatif dan tugas hakim secara kongkrit dalam mengadili suatu perkara. Beberapa tugas dan kewajiban pokok hakim dalam bidang peradilan secara normatif telah diatur dalam dalam UU No. 48 Tahun 2009 antara lain: a. Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. (Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009) b. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. (Pasal 2 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009) c. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. (Pasal 3 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009) d. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedabedakan orang (Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009) e. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan Bab 5 267 yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009) f. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009) g. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. (Pasal 5 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009) h. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Pasal 5 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009) i. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. (Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009). j. Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. (Pasal 11 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009) k. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. (Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009) l. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. (Pasal 13 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009) m. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan (Pasal 14 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009). Di samping tugas hakim secara normatif sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan, hakim juga mempunyai tugas secara kongkrit dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara melalui tiga tindakan secara bertahap, yaitu: a. Mengkonstatir (mengkonstatasi) yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa kongkrit. Hakim mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan para pihak di muka persidangan. Syaratnya adalah peristiwa kongkrit itu harus dibuktikan terlebih dahulu, tanpa pembuktian hakim tidak boleh menyatakan suatu peristiwa kongkrit itu benar-benar terjadi. Jadi mengkonstatir berarti menetapkan peristiwa kongkrit dengan membuktikan pristiwanya atau menganggap telah terbuktinya peristiwa tersebut. 268 Landasan Aksiologi... b. Mengkwalifisir (mengkwalifikasi) yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa hukumnya. Hakim menilai peristiwa yang telah dia-nggap benar-benar terjadi itu termasuk dalam hubungan hukum yang mana atau seperti apa. Dengan kata lain mengkwalifisir adalah menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstatir dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut. Mengkwalifikasi dilakukan dengan cara mengarahkan peristiwanya kepada aturan hukum atau undangundangnya, agar aturan hukum atau undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya undang-undangnya juga harus disesuaikan dengan peristiwanya agar undang-undang tersebut dapat mencakup atau meliputi peristiwanya. c. Mengkonstituir (mengkonstitusi) atau memberikan konstitusinya, yaitu hakim menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada para pihak yang bersangkutan. Di sini hakim mengambil kesimpulan dari adanya premisse mayor (peraturan hukumnya) dan premisse minor (peristiwanya). Dalam memberikan putusan, hakim perlu memperhatikan faktor yang seharusnya diterapkan secara proporsional yaitu keadilan (Gerechtigkeit), kepastian hukumnya (Rechtssicherheit) dan kemanfaatannya (Zweckmassigkeit). Gr. Van der Brught dan J.D.C. Winkelman menyebutkan tujuh langkah yang harus dilakukan seorang hakim dalam menyelesaikan suatu kasus atau peristiwa, yaitu:51 a. Meletakkan kasus dalam sebuah peta (memetakan kasus) atau memaparkan kasus dalam sebuah ikhtiar (peta), artinya memaparkan secara singkat duduk perkara dari sebuah kasus (menskematisasi). b. Menerjemahkah kasus itu ke dalam peristilahan yuridis (mengkwalifikasi, pengkwalifikasian). c. Menyeleksi aturan-aturan hukum yang relevan. d. Menganalisis dan menafsirkan (interpretasi) terhadap aturan-aturan hukum itu. e. Menerapkan aturan-aturan hukum pada kasus. f. Mengevaluasi dan menimbang (mengkaji) argumen-argumen dan penyelesaian. g. Merumuskan formulasi penyelesaian. Gr. Van der Brught dan J.D.C. Winkelman sebagaimana dikutip oleh Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks KeIndonesiaan, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2004, hlm. 177. 51 Bab 5 269 Di samping itu dalam melaksanakan dan memimpin jalannya proses persidangan, pada prinsipnya Majelis Hakim tidak diperkenankan menunda-nunda persidangan tersebut. Pasal 159 ayat 4 HIR atau Pasal 186 ayat (4) RBg menyebutkan bahwa pengunduran (penundaan) tidak boleh diberikan atas permintaan kedua belah pihak dan tidak boleh diperintah-kan Pengadilan Negeri karena jabatannya, melainkan dalam hal yang teramat perlu. Dalam praktik hakim terkadang terlalu lunak sikapnya terhadap permohonan penundaan sidang dari para pihak atas kuasanya. Adapun beberapa hal yang sering menyebabkan tertundanya sidang antara lain: 1. Tidak hadirnya para pihak atau kuasanya secara bergantian. 2. Selalu minta ditundanya sidang oleh para pihak. 3. Tidak datangnya saksi walau sudah dipanggil. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka diperlukan peranan hakim yang aktif terutama dalam mengatasi hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat (speedy administration of justice). Perlu ketegasan hakim untuk menolak permohonan penundaan sidang daripada pihak, kalau ia beranggapan hal itu tidak perlu. Berlarutlarutnya atau tertunda-tundanya jalannya peradilan akan mengurangi kepercayaan masyarakat kepada peradilan yang mengakibatkan berkurangnya kewibawaan pengadilan (justice delayed is justice denied). 3. Eksistensi Peradilan dalam Menegakkan Keadilan Dalam rangka menegakkan aturan-aturan hukum yang berlaku, maka diperlukan adanya suatu institusi negara yang dinamakan kekuasaan kehakiman (Judicative power). Kekuasaan kehakiman dalam praktik diselenggarakan oleh badan-badan peradilan negara. Adapun tugas pokok badan peradilan terutama tugas di bidang judicial, yaitu dalam rangka memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan. Terkait dengan keberadaan pencari keadilan khususnya yang kurang mampu secara ekonomi, sekarang ini sudah ada salah satu upaya 270 Landasan Aksiologi... pemecahannya untuk beracara secara prodeo. Tepat tanggal 31 Desember 2008, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 83 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Peraturan pemerintah ini dikeluarkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Menurut PP tersebut, seorang advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan (Pasal 2). Bantuan hukum secara cuma-cuma meliputi tindakan hukum untuk kepentingan pencari keadilan di setiap tingkat proses peradilan dan berlaku juga terhadap pemberian jasa hukum di luar pengadilan. Meskipun demikian implementasi PP ini perlu dilakukan evaluasi oleh pihak-pihak terkait apakah sudah berjalan dengan baik ataukah sebaliknya. Tentunya diharapkan PP ini dapat berjalan optimal nantinya, sehingga akses mendapatkan keadilan (acces to justice) dapat lebih merata, karena keadilan bukan hanya milik orang yang kaya saja, tetapi milik mereka yang papa.52 Para pencari keadilan (justiciabellen) tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakimhakim yang professional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan putusan-putusan yang tidak saja mengandung aspek kepastian hukum (keadilan procedural), tetapi juga berdimensikan legal justice, moral justice dan social justice. Karena keadilan itulah yang menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan.53 Keadilan itu sesungguhnya berhubungan dengan hati nurani, bukan definisi dan juga bukan soal formal-formalan. Ia berhubungan erat dengan praksis kehidupan sehari-hari dari manusia. Bukan soal teori-teori ilmu hukum sebagaimana diterapkan oleh Majelis Hakim Agung pada perkara Akbar Tanjung itu. Kelihatannya, menurut teori Bambang Sutiyoso, Bantuan Hukum Cuma-Cuma, lihat di http:// bambang.staff.uii.ac.id/index.php 53 Bambang Sutiyoso, Op.Cit., hlm. 2. 52 Bab 5 271 ilmu hukum putusan tersebut bagus, argumentatif ilmiah. Tetapi sebenarnya, belum menyentuh rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga tepatlah apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch : “Summum ius summa inuiria”, bahwa keadilan teringgi itu adalah hati nurani. Orang yang terlalu mematuhi hukum secara apa adanya seringkali justru akan merugikan keadilan.54 Menegakkan keadilan bukanlah sekadar menjalankan prosedur formal dalam peraturan hukum yang berlaku di suatu masyarakat, setidaknya itulah pernyataan yang kerap dicetuskan oleh Moh Mahfud MD., Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Menurut Mahfud, menegakkan nilai-nilai keadilan lebih utama daripada sekadar menjalankan berbagai prosedur formal perundang-undangan yang acapkali dikaitkan dengan penegakan hukum.55 Tekad Mahkamah Konstitusi semacam itu bahkan ditegaskan dalam situsnya, yaitu “mengawal demokrasi dan menegakkan keadilan substantif”. Beberapa terobosan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang lebih mengutamakan keadilan substantif dibanding keadilan formalprosedural di antaranya adalah saat Mahkamah Konstitusi membolehkan penggunaan KTP dengan sejumlah syarat tertentu dalam pemilu oleh warga yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Di samping itu Mahkamah Konstitusi dalam persidangan judicial review pernah membuka rekaman hasil penyadapan KPK terhadap percakapan Anggodo yang kemudian membuka tabir adanya “markus” dalam proses penegakan hukum. Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, seringkali para penegak hukum sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan main yang ada, dalam artian aturan main yang formal. Terhadap kasus tindak pidana korupsi misalnya, sesuai hukum yang berlaku, jaksa sudah Jeremies Lemek. 2007. Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakkan Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Galang Press. Hlm. 25. 55 Lihat artikel “Menegakkan Keadilan Jangan Sekedar Menegakkan Hukum” dalam situs http://erabaru.net/opini/65-opini/10099-menegakkan-keadilan-jangan-sekedarmenegakkan-hukum, diakses tanggal 20 April 2010. 54 272 Landasan Aksiologi... melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan ke pengadilan. Pengacara sudah menjalankan fungsinya untuk membela dan mempertahankan hak-hak tersangka. Hakim sudah mendengar kedua belah pihak, sehingga turunlah putusan pengadilan. Semua aturan hukum yang relevan sudah dipertimbangkan dan sudah diterapkan. Akan tetapi mengapa terhadap penegakan hukum yang demikian masih saja banyak masyarakat yang tidak puas. Inilah masalahnya, yaitu tidak terpenuhinya nilai keadilan, terutama keadilan masyarakat (social justice). Hakim tidak dengan sungguh-sungguh menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan alasan terikat dengan aturan hukum formal yang sebenarnya kaku bahkan dalam beberapa hal justru melenceng. Padahal Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sudah mewajibkan kepada para hakim untuk menggali hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.56 Karena itu agar penegakan hukum di Indonesia dapat lebih baik dan agar masyarakat percaya pada hukum yang berlaku, yang diperlukan adalah penegakan hukum yang berkeadilan, dan itulah yang didamba-dambakan oleh masyarakat banyak. Untuk itu dalam panggung penegakan hukum di Indonesia, dibutuhkan kehadiran para penegak hukum yang bervisi keadilan, dan penguasa yang bersikap adil, sebagaimana dalam cita hukum tradisional bangsa Indonesia diistilahkan dengan “ratu adil” atau seperti yang diimpikan oleh filosof besar bangsa Yunani, yaitu Plato dengan konsep “raja yang berfilsafat” (filosopher king) ribuan tahun yang silam.57 Kalau dicermati kepala putusan hakim itu sendiri berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu pertimbangan keadilan sesungguhnya lebih dikedepankan dalam memutus suatu perkara. Dalam hal ini memang sepenuhnya diserahkan kepada majelis hakim yang menangani perkara tersebut. 56 57 Lihat Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Munir Fuady, Op. Cit., hlm. 53. Dikutip dengan beberapa perubahan dari penulis. Bab 5 273 Bismar Siregar dalam bukunya “Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan” menambahkan bahwa dasar seorang hakim dalam mengambil putusan adalah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhahan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, dalam menetapkan putusannya, pertama-tama seorang hakim bermunajat kepada Alloh SWT. Atas nama-NYAlah suatu putusan diucapkan. Ia bersumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Pada saat itulah hatinya bergetar. Ini merupakan peringatan bagi siapa saja. Pesan Rasululloh Mohammad SAW kepada seorang sahabatnya sebagai berikut: “Wahai Abu Hurairah, keadilan satu jam lebih utama dari ibadahmu puluhan tahun, shalat, zakat dan puasa. Wahai Abu Hurairah, penyelewengan hukum satu jam lebih pedih dan lebih besar dalam pandangan Alloh daripada melakukan maksiat enampuluh tahun”. Sebuah pesan yang indah, yang wajib dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh para hakim.58 Dalam ajaran Islam juga diperintahkan agar kita bertindak adil dalam menyelesaikan suatu perkara. Perintah itu antara lain disebutkan dalam Al Qur’an Surat An- Nisa: 58, disebutkan: “Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”. Selanjutnya dalam Al Qur’an Surat An-Nisa: 135 ditegaskan: Wahai orang-orang yang beriman, jadilan kamu orang-orang yang benarbenar penegak keadilan, menjadi saksi karena Alloh biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Alloh lebih tahu kemaslahatannya , maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan men jadi saksi, maka sesungguhnya Alloh adalah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”. Keadilan merupakan salah satu tujuan dari setiap sistem hukum, bahkan merupakan tujuannya yang terpenting. Masih ada tujuan hukum yang lain yang juga selalu menjadi tumpuan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan ketertiban. Di samping tujuan hukum, keadilan dapat juga dilihat sbagai suatu nilai (value). Bagi suatu kehidupan 58 Bismar Siregar. 1995. Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan. Jakarta: Gema Insani Press. Hlm. 19-20. 274 Landasan Aksiologi... manusia yang baik, ada empat nilai yang merupakan fondasi pentingnya, yaitu: (1) Keadilan; (2) Kebenaran; (3) Hukum dan (4) Moral. Akan tetapi dari keempat nilai tersebut, menurut filosof besar bangsa Yunani, yaitu Plato, keadilan merupakan nilai kebajikan yang tertinggi. Menurut Plato: “ Justice is the supreme virtue which harmonize all other virtues”.59 Para filosof Yunani memandang keadilan sebagai suatu kebajikan individual (individual virtue). Oleh karena itu dalam Institute of Justinian, diberikanlah definisi keadilan yang sangat terkenal itu, yang mengartikan kadilan sebagai suatu tujuan yang kontinyu dan konstan untuk memberikan kepada setiap orang haknya. “Justice is the constant and continual purpose which gives to everyone his own”.60 Mahkamah Agung sendiri dalam intruksinya No. KMA/015/INST/ VI/1998 tanggal 1 Juni 1998 mengintruksikan agar para hakim memantapkan profesionalisme dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas, dengan menghasilkan putusan hakim yang eksekutabel, berisikan ethos (integritas), pathos (pertimbangan yuridis yang utama), filosofis (berintikan rasa keadilan dan kebenaran), sosiologis (sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat), serta logos (dapat diterima akal sehat), demi terciptanya kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman.61 Apabila dicermati, para hakim di Indonesia pada umumnya tidak menganut prinsip the binding force of precedent sebagaimana dianut negaranegara Anglosaxon, oleh karena itu otoritas dari majelis hakim menjadi begitu besarnya dalam memutuskan perkara. Akibatnya kemudian banyak terjadi disparitas putusan dalam perkara yang sejenis. Hal ini ditandai dengan adanya perbedaan secara substansial yang tajam antara produk hukum berupa putusan pengadilan yang satu dengan pengadilan yang lain atau putusan yang dibuat oleh hakim Pengadilan Negeri, hakim Roscoe Pound sebagaimana dikutip Munir Fuady. 2003. Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 52. 60 Ibid. Hlm. 53. 61 A. Mukti Arto. 2006. Mencari Keadilan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 98. 59 Bab 5 275 Pengadilan Tinggi, dan hakim Mahkamah Agung mengenai suatu perkara hukum yang sama, padahal semuanya mengacu pada peraturan yang sama. Perbedaan tersebut memang dimungkinkan, karena praktek penegakan hukum terlibat berbagai kepentingan yang berbeda di balik hukum yang hendak ditegakkan.62 Para hakimpun punya dalih, apabila pencari keadilan (justiciabellen) merasa tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan, mereka dipersilahkan mengajukan upaya hukum yang ada. Dengan demikian peran hakim memang sangat dominan dalam menentukan bagaimana ’hitam putihnya’ suatu putusan. Meskipun demikian di sisi lain, kualitas dan kredibilitas seorang Hakim juga ditentukan oleh putusan-putusan yang dibuatnya. Tidak berlebihan kalau ada pendapat yang mengatakan bahwa mahkota atau wibawa hakim terletak pada putusannya atau kalau mau lebih dalam lagi ada pada pertimbangan hukumnya. Oleh karena itu kewibawaan hakim juga akan luntur dengan sendirinya kalau putusan-putusannya tidak berpihak lagi kepada nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Sehubungan dengan itu menurut Paulus Effendi Lotulung, Hakim Agung, untuk mencari hakim yang jujur dan berkualitas, sesungguhnya tidak perlu metode yang berbelit-belit, cukup dilihat dari putusanputusan yang telah dihasilkannya selama ini. Salah satu caranya adalah dengan cara eksaminasi putusan,63 yang sesungguhnya telah lama dikenal dalam dunia peradilan di Indonesia berdasarkan ketentuan SEMA No. 1 Tahun 1967 tentang Eksaminasi, Laporan Bulanan, dan Daftar Banding. Secara umum yang dimaksud eksaminasi adalah menguji kembali putusan hakim dengan melihat isi/materi dari putusan tersebut. Eksaminasi juga bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan akuntabilitas seperti yang selama ini disuarakan oleh masyarakat. Mudzakkir, 2003. Urgensi dan Relevansi Eksaminasi Publik. Makalah dalam diskusi panel yang diselenggarakan oleh Departemen Acara FH UII, Pusdiklat Laboratorium UII, ICW dan ICM, Yogyakarta, 28 Juni 2003. Hlm. 2 63 www. hukumonline.com, Cari Hakim Jujur Lewat Eksaminasi Putusannya, diakses tanggal 18 Februari 2007. 62 276 Landasan Aksiologi... Melalui eksaminasi, masyarakat bisa mengetahui dasar pertimbangan seorang hakim dalam mengambil putusannya. Dari situ, bisa dinilai pula apakah putusan hakim tersebut diambil dengan cara-cara yang semestinya atau malah sarat dengan nuansa KKN.64 Dalam kaitan ini, eksaminasi dilakukan untuk memberikan penilaian secara komprehensif oleh ahli yang kompeten terkait putusan hakim tertentu terutama menyangkut penerapan hukum materiil maupun hukum formilnya dalam kerangka penilaian secara obyektif menyangkut perkara yang bersangkutan. 4. Konsep Keadilan Putusan dalam Peradilan Dalam diskursus konsep keadilan (justice), banyak ditemukan berbagai pengertian keadilan, diantaranya keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya (proporsional); keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan lain sebagainya. Demikian pula klasifikasi keadilan juga banyak ditemukan misalnya Aristoteles membagi keadilan komutatif dan distributif, ada juga membedakan norm gerechtigkeit dan einzelfall gerechtigkeit dan seterusnya. Demikian ada ahli yang membagi menjadi: keadilan hukum (legal justice), keadilan secara moral (moral justice) dan keadilan sosial (social justice). Di samping itu dikenal juga istilah keadilan transendental (transcendental justice) yang sebenarnya lebih mendekati pada pengertian keadilan profetik.65 John Rawls menyatakan bahwa keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar. Demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisen dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan Ibid. Keadilan transendental adalah keadilan yang yang spirit atau jiwanya dengan mendasarkan pada nilai-nilai keadilan ilahiyah yang didasarkan pada kitab suci Al Qur’an. Keadilan transendental inilah yang diperjuangkan dan dicontohkan oleh para nabi dan Rasul, sehingga bisa disebut juga sebagai keadilan profetik. 64 65 Bab 5 277 jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang didasarkan pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkanya. Atas dasar itu keadian menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Karena itu, dalam masyarakat yang adil kebebasan warganegara dianggap mapan, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial. Satu-satunya hal yang mengijinkan kita untuk menerima teori yang salah adalah karena tidak adanya teori yang lebih baik, secara anaogis ketidakadilan bisa dibiarkan hanya ketika ia butuh menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Sebagai kebajikan utama ummat manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat. Proposisi tersebut tampak menunjukkan keyakinan intuitif kita tentang keutamaan keadilan.66 Dalam konteks putusan hakim peradilan, terutama yang sering disinggung-singgung adalah berupa keadilan prosedural (procedural justice) dan keadilan substantif (substantive justice). Dalam hal ini kami mencoba memberi batasan apa yang dimaksud dengan keadilan prosedural dan keadilan substantif ini. Keadilan prosedural adalah keadilan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dari peraturan hukum formal, seperti mengenai tenggat waktu maupun syarat-syarat beracara di pengadilan lainnya. Sedangkan keadilan substantif adalah keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang responsif sesuai hati nurani. Dengan demikian konsep keadilan sebenarnya sudah banyak dikemukakan oleh para ahli karena keadilan sesungguhnya sesuatu yang sangat dekat dengan pemenuhan hak dan kepentingan manusia. Hanya saja yang tidak mudah dalam praktek adalah merumuskan apa yang John Rawls. 2006. Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara. Yogyakarta: Pusaka Pelajar. Hlm. 4. 66 278 Landasan Aksiologi... menjadi tolok ukur atau parameter keadilan itu sendiri. Proses penyelesaian perkara di pengadilan melibatkan setidaknya dua pihak yang masingmasing sedang terlibat konflik kepentingan (conflict of interest) satu dengan lainnya. Sehingga bisa saja terjadi ketika putusan hakim dijatuhkan akan dirasakan berbeda oleh kedua belah pihak, yaitu satu pihak merasa adil karena keinginannya dikabulkan, tetapi pihak yang lain merasa putusannya tidak adil karena keinginannya tidak dapat terpenuhi. Sehingga hakekatnya persoalan keadilan itu implementasinya dalam praktik dirasakan adil atau tidak adil adalah berdasarkan penilaian masing-masing pihak, yang sangat mungkin berbeda secara diametral parameternya. Dalam tataran ideal, untuk mewujudkan putusan hakim yang memenuhi harapan pencari keadilan, yang mencerminkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi dengan baik. Gustav Radbruch mengemukakan idealnya dalam suatu putusan harus memuat idee des recht, yang meliputi 3 unsur yaitu keadilan (Gerechtigkeit), kepastian hukum (Rechtsicherheit) dan kemanfaatan (Zwechtmassigkeit).67 Ketiga unsur tersebut semestinya oleh Hakim harus dipertimbangkan dan diakomodir secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan. Mochtar Kusumaatmadja68 mengemukakan bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, bebas dari campur tangan masyarakat, eksekutif maupun legislatif. Dengan kebebasan yang demikian itu, diharapkan hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinannya yang seadil-adilnya serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian maka hukum dan badan-badan pengadilan akan dapat Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo. 2004. Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty. Hlm. 15. 68 Muchtar Kusumaatmadj. 1986. Fungsi dan Perkembangan hukum dalam Pembangunan Nasional, Lembaga Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Bandung: Penerbit Bina Cipta. Hlm. 319-320. 67 Bab 5 279 berfungsi sebagai penggerak masyarakat dalam pembangunan hukum dan pembinaan tertib hukum. Dalam implementasinya terkadang tidak mudah untuk mensinergikan ketiga unsur tersebut di atas, terutama antara unsur keadilan dengan kepastian hukum bisa saja saling bertentangan. Di samping beberapa contoh kasus yang sudah disebutkan sebelumnya, kasus lama yang masih cukup relevan untuk menggambarkan adanya kemungkinan benturan antara aspek keadilan (substantif) dan kepastian hukum (keadilan prosedural), yaitu dalam kasus “Kedung Ombo” di Jawa Tengah. Kasus ini berkaitan dengan sengketa ganti rugi pembebasan tanah yang akan digunakan sebagai proyek waduk “Kedung Ombo” di Jawa Tengah, antara warga masyarakat dan Gubernur Jawa Tengah. Gugatan pada awalnya diajukan pada tahun 1990 di Pengadilan Negeri Semarang, kemudian berlanjut dengan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Semarang, Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Pihak Penggugat adalah warga masyarakat yang dibebaskan tanahnya untuk pembangunan waduk Kedung Ombo, sedang tergugatnya adalah Gubernur Jawa Tengah (Terggugat I) yang dianggap telah menetapkan ganti rugi secara sepihak tanpa musyawarah dan pimpinan proyek waduk Kedung Ombo (Tergugat II). Dalam tuntutannya, antara lain penggugat minta tergugat memberikan ganti rugi tanahnya sebesar Rp. 10.000,00 permeter2, karena tanah milik para penggugat sudah tidak dapat digunakan lagi. Sehubungan dengan gugatan tersebut, PN Semarang dalam putusannya No. 117/Pdt/G/1990/PN.Smg menyatakan menolak gugatan para penggugat seluruhnya. Dalam upaya hukum banding, Pengadilan Tinggi Semarang kembali menguatkan putusan sebelumnya, dengan tetap menolak gugatan. Selanjutnya dalam tingkat kasasi, Majelis hakim kasasi menjatuhkan putusan yang dianggap fenomenal. Dalam putusannya No. 2263.K/Pdt/1991, Majelis hakim kasasi yang dipimpin oleh Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH. Menghukum pihak tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng, berupa antara lain : 280 Landasan Aksiologi... a. Kerugian materiel untuk tanah dan atau bangunan Rp. 50.000,00/ M2, sedangkan untuk tanaman-tanaman sebesar Rp. 30.000,00/M2. b. Kerugian yang timbul yang bersifat immateriel, yaitu sesuai dengan petitum secara Ex Aequeo et Bono sebesar Rp. 2000.0000.000,00.69 Tak mengherankan putusan kasasi tersebut menjadi perbincangan di kalangan hukum, ada yang sependapat ada pula yang kontra atas putusan. Secara yuridis normatif, putusan kasasi ini memang berupaya menerobos ketentuan hukum dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, yang berbunyi: “Hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan, tatapi Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak dituntut atau mengabulkan putusan lebih daripada yang dituntut.” Dalam hal ini terlihat bahwa pada gugatan awalnya penggugat hanya menuntut ganti rugi atas tanahnya sebesar Rp. 10.000,00/M2 tetapi dalam putusan kasasi dikabulkan ganti rugi atas tanahnya sebesar Rp. 50.000,00/M2. Di samping itu majelis hakim kasasi juga mengabulkan ganti rugi immateriel sebesar Rp. 2000.000.000,00, yang pada umumnya jarang dikabulkan dalam suatu putusan. Meskipun demikian, majelis hakim kasasi beralasan bahwa putusan tersebut dijatuhkan atas pertimbangan aspek keadilan, tidak semata-mata pada aspek kepastian hukum. Memang dilihat dari sisi kepastian hukum bisa dikatakan melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR, tetapi dari sisi keadilan perlu diperhatikan bahwa harga tanah tidak mungkin konstan/tetap dari waktu kewaktu apalagi sudah berjalan beberapa tahun, sehingga sudah sepantasnya ganti rugi atas tanah juga disesuaikan dengan keadaan riel pada saat itu. Sehingga dapat dikatakan ketika terjadi benturan antara aspek keadilan dengan kepastian hukum, majelis kasasi lebih mendahulukan aspek keadilannya. Banyak yang menyayangkan ketika pada akhirnya dalam upaya hukum peninjauan kembali, majelis hakim peninjauan kembali kemudian menganulir putusan kasasi Mahkamah Agung, karena dianggap asas 69 Lihat amar putusan kasasi Mahkamah Agung No. 2263.K/Pdt/1991. Bab 5 281 hukum dan ketentuan yang berlaku, terutama yang diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR. Majelis hakim peninjauan kembali nampaknya di sini lebih mentikberatkan pada aspek kepastian hukumnya (keadilan proseduralnya) dibandingkan aspek keadilan (substantifnya) dalam menjatuhkan putusannya.70 Di Indonesia sebagai suatu negara hukum, hak seseorang terhadap tanah harus dilindungi, tetapi masyarakat harus menyadari bahwa tanah memunyai fungsi sosial yakni lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Tetapi di sini yang menjadi masalah adalah kata-kata ’kepentingan umum’, seperti tanah yang akan dibebaskan itu demi kepeningan umum yakni akan dibangun suatu bangunan atau poyek yang berguna bagi masyarakat banyak, namun para pemilik tanh yang mengolah atau memanfaatkan tanahnya sebagai tempat tinggal atau kepentingan lain adalah juga termasuk kepentingan umum. Karena itu juga menyangkut kepentingan orang banyak. Tapi yang dimaksud kepentingan umum di sini adalah kepentingan yang lebih banyak menyangkut orang banyak. Dari kedua kepentingan tersebut, seakan-akan dua kepentingan umum saling bertabrakan.71 Jika suatu lokasi yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan umum tersebut harus lokasi yang benar-benar bisa digunakan untuk pembangnan kepentingan umum dan pelaksanaannya bisa berbentuk badan pemerintah atau swasta. Tidak semua tempat bisa dicabut haknya dengan alasan demi kepentingan umum. Tanah yang bisa dicabut haknya hanyalah tanah yang berlokasi termasuk dalam “Rencana Induk Pengembangan” daerah setempat. Dan pengesahan rencana induk tersebut telah mendapat persetujuan dari wakil rakyat di DPRD. Dan rencana induk tersebut harus bersifat terbuka untuk umum.72 Dalam contoh ilustrasi kasus lainnya adalah masalah penegakan peraturan hukum lalu lintas seharusnya dipatuhi oleh setiap pengguna Bambang Sutiyoso, Op.Cit., hlm. 24 Mudakir Iskandar Syah. 1985. Hukum Dan Keadilan. Jakarta: Grafindo Utama. Hlm. 46-47. 72 Ibid, hlm. 47-48. 70 71 282 Landasan Aksiologi... jalan. Sehingga ketika lampu trafict light menyala merah, semestinya pengguna jalan berhenti. Tetapi dalam kasus tertentu dan dengan argumen tertentu, mobil ambulance, kereta api dan mobil pemadam kebakaran boleh jalan terus meskipun harus menerobos lampu merah. Tetapi bagi pengguna jalan masyarakat umum, mestinya aturan tersebut harus tetap ditegakkan, karena kalau semua pengguna jalan diperbolehkan menerobos lampu merah yang terjadi adalah kekacauan, kecelakaan dan saling tabrakan. Paparan kasus di atas, sama sekali tidak dimaksudkan untuk menjustifikasi apalagi menghakimi siapa yang salah dari fenomena yang terjadi, tetapi mencoba mengurai pokok persoalannya secara jernih. Itu disebabkan realitas yang terungkap dalam praktik penegakan hukum bukan merupakan sesuatu yang seketika terjadi, melainkan sebagai hasil interaksi dari proses sebab akibat dalam perspektif yang lebih luas. Semestinya antara keadilan prosedural dan keadilan substantif tidak dilihat secara dikotomi, tetapi ibarat dua sisi mata uang yang saling terkait erat satu sama lain. Oleh karena itu dalam keadaan normal, mestinya keadilan prosedural dan substantif harus dapat disinergikan dan diakomodir secara proporsional. Meskipun demikian dalam batas-batas tertentu, sangat mungkin keduanya saling berbenturan satu sama lain dan tidak dapat dikompromikan. Adanya benturan-benturan antara pemenuhan keadilan prosedural di satu sisi dan keadilan substantif di sisi lain, memang harus ada solusi dan opsi yang jelas dan harus diputuskan oleh Hakim dengan argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini kami berpendapat, semestinya hakim lebih dahulu mengedepankan pilihan keadilan substantif, yang sesuai dengan hati nurani dan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, hanya dalam hal-hal kasuistik dan sangat eksepsional, yaitu terjadi pertentangan yang tajam antara keadilan prosedural dan keadilan substantif, keadilan prosedural bisa diabaikan. Akan tetapi, tentunya tidak berarti semua kasus harus boleh begitu saja keadilan prosedural dikalahkan. Hal ini untuk menghindari Bab 5 283 apa yang dikemukakan oleh Machiavelli, yaitu dihalalkannya segala cara untuk mencapai tujuan, atau dengan kata lain jangan sampai keadilan prosedural diabaikan begitu saja untuk mencapai tujuan tertentu yang sebenarnya tidak terlalu essensial pemenuhannya. 5. Keadilan Profetik dan Implementasinya dalam Peradilan Apabila dicermati dalam kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka hakikatnya keadilan yang hendak diputuskan adalah keadilan transendental (trancendental justice). Keadilan seperti ini tentunya keadilan yang penuh dengan makna dan nilai-nilai ilahiyah yang menjiwai dalam suatu putusan. Bagi hakim keadilan yang hendak diputuskan tidak hanya dipertanggungjwabkan secara horisontal kepada sesama manusia, baik pencari keadilan maupun masyarakat, tetapi juga dipertanggungjawabkan secara vertikal kepada Tuhan Seru Sekalian Alam. Apa yang telah diputus oleh hakim didunia tentunya masih belum selesai, karena hakim juga harus mempertanggungjawabkan kepada yang Maha Hakim kelak. Keadilan transendental sesungguhnya spirit dan jiwanya sangatlah ideal, karena parameter keadilan yang hendak dikonstruksikan adalah keadilan sebagaimana diperintahkan dan diajarkan oleh Tuhan dalam kitab suci. Kitab suci adalah pedoman utama dalam menggali dan merumuskan nilai-nilai keadilan dalam suatu putusan. Keadilan seperti itulah yang dicontohkan oleh para Nabi dan Rosul. Konsep keadilan seperti itulah yang dimaksudkan sebagai keadilan profetik. Keadilan profetik ini tentunya juga sejalan dan dapat sinergi dengan nilai keadilankeadilan lainnya, terutama keadilan substantif, yang mempertimbangkan nilai-nilai substantif dalam putusannya, tidak semata-mata berdasarkan keadilan prosedural. Persoalan dalam praktek peradilan sekarang ini yang masih banyak ketimpangan dalam penerapan keadilan dan jauh dari harapan masyarakat adalah karena konsep keadilan transendental atau keadilan 284 Landasan Aksiologi... profetik yang ada dalam kepala putusan hakim ternyata tidak diterapkan dengan sungguh-sungguh. Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang seharusnya menjadi jiwa dalam putusan, tetapi dalam isi putusan ternyata kering dari nilai-nilai Ketuhanan itu sendiri. Jarang sekali dalam suatu putusan mengaitkan dengan nilai-nilai keadilan yang ada dalam kitab suci Al Qur’an. Dalam praktik justru hakim lebih banyak bemain dengan retorika kita undang-undang buatan manusia. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab banyaknya putusan hakim yang kontroversial dan sulit memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan. Karena spirit yang ada dfalam kepala putusan dianggap hanya formalitas yang harus dipenuhi, tetapi isinya justru banyak menggunakan logika hukum normatif yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Dari sisi persepsi teori penulisan hukum, pembuatan putusan seperti itu sebenarnya mencerminkan ketidaksinkronan antara judul (kepala putusan) dengan substansinya (isi putusannya). Berdasarkan dari berbagai diskusi dan perbincangan dengan beberapa hakim dengan penulis, kendala utama penegakan hukum profetik adalah karena yang menjadi dasar utama penegakan hukum di Indonesia adalah bersumber pada hukum positif, bukan secara langsung mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam kitab suci. Di samping itu Hakim akan merasa kesulitan kalau harus mengaitkan kasusnya dengan mendasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam kitab suci, karena selama ini yang diajarkan dan dicontohkan dalam pendidikan hukum juga dengan mendasarkan pada hukum positif. Tetapi secara tersirat, ada keinginan dan harapan juga diantara para Hakim untuk menerapkan keadilan profetik dalam putusan-putusannya sebagaimana dicontohkan Hakim Bismar Siregar. Untuk itu perlu ada kebijakan, pedoman dan pengaturan yang jelas kalau memang keadilan profetik menjadi suatu alternatif yang dapat memenuhi harapan para pencari keadilan di tanah air ini. Bab 5 285 6. Penutup Perbincangan mengenai pencarian format ideal keadilan putusan dalam peradilan masih membuka ruang kajian yang lebih dalam, karena kompleksitasnya masalah penegakan hukum di Indonesia, termasuk banyaknya konsep keadilan, implementasinya serta penentuan tolok ukur keadilan itu sendiri masih berbeda-beda. Tetapi khusunya terkait dengan wacana penegakan keadilan profetik dalam lembaga peradilan, selama ini masih sebatas wacana, meskipun sebenarnya kalau didasarkan pada spirit dan jiwa yang ada dalam kepala putusan, memungkinkan bagi hakim untuk menerapkan keadilan profetik. Persoalan dalam praktek peradilan sekarang ini yang masih banyak ketimpangan dalam penerapan keadilan dan jauh dari harapan masyarakat adalah karena konsep keadilan transendental atau keadilan profetik yang ada dalam kepala putusan hakim ternyata tidak diterapkan dengan sungguh-sungguh. Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang seharusnya menjadi jiwa dalam putusan, tetapi dalam isi putusan ternyata kering dari nilai-nilai Ketuhanan itu sendiri. Tetapi kenyataannya jarang sekali dalam suatu putusan mengaitkan dengan nilai-nilai keadilan yang ada dalam kitab suci Al Qur’an. Dalam praktik justru hakim lebih banyak bemain dengan retorika kita undang-undang buatan manusia. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab banyaknya putusan hakim yang kontroversial dan sulit memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan. Karena spirit yang ada dalam kepala putusan dianggap hanya formalitas yang harus dipenuhi, tetapi isinya justru banyak menggunakan logika hukum normatif yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Untuk itu ke depan perlu ada kebijakan, pedoman dan pengaturan yang jelas kalau memang keberadaan keadilan profetik menjadi suatu alternatif yang dianggap dapat memenuhi harapan para pencari keadilan di tanah air ini. 286 Landasan Aksiologi... BAB 6 PENUTUP Oleh M. Syamsudin A. Menangkap Peluang di Era Postmodern Perkembangan pemikiran orang tentang suatu realitas, termasuk realitas hukum sejak Zaman Kuno sampai dengan Zaman Postmodern saat ini mengalami perubahan-perubahan yang sangat fundamental. Perubahan fundamental tersebut terjadi pada setiap era/zamanya masing-masing, sehingga masing-masing era/zaman mempunyai ciri yang khas dan berbeda. Pada umumnya para ahli sejarah peradaban dunia membagi periodisasi era/zaman dimulai dari Zaman Kuno, abad ke-5 SM sampai abad ke-5 M, Zaman Pertengahan/Klasik, abad ke-6 sampai abad ke-14 M, Zaman Modern, abad ke-15 sampai 20 M, dan terakhir Zaman Postmodern, abad ke-21 dan seterusnya. Corak pemikiran orang pada Zaman Kuno, yang berpusat di Yunani-Romawi, umumnya bersifat cosmosentris, artinya alam semesta (cosmos) menjadi pusat perhatian dan pemikiran utama para filosuf pada waktu itu. Para filusuf (kaum Sofis) banyak memusatkan pemikirannya pada keberadaan alam semesta. Dari corak cosmosentris tersebut, produk filsafat yang lahir adalah filsafat cosmologi. Mereka sangat concern memikirkan alam semesta terutama dari segi hakikat (inti) dan kejadiannya. Misalnya Thales (624-548 SM), yang menyatakan bahwa hakikat (inti) alam adalah air, Anaximenes, yang menyatakan bahwa inti alam adalah udara, Hiraklitos, yang menyatakan bahwa inti 288 Penutup alam adalah api, dan Pitagoras (532 SM), yang menyatakan bahwa inti alam adalah bilangan. Pada zaman Kuno tersebut orang memandang realitas hukum (hakikat hukum) juga tidak terlepas dari prinsip-prinsip tentang ajaran cosmologi. Pada zaman ini cara berpikir orang tentang hukum banyak didominasi oleh paham yang ada waktu itu yang disebut paham hukum kodrat atau paham hukum alam, baik yang coraknya irrasional maupun rasional. Hukum pada waktu itu dipandang sebagai asas-asas moralitas dan keadilan yang bersifat universal yang sumbernya adalah cosmos baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu supranaturalthing (tuhan). Cara berpikir dan juga berhukum seperti digambarkan pada zaman kuno itu kemudian mengalami perubahan setelah memasuki Zaman Pertengahan (klasik) pada awal abad ke-6 M. Pada zaman ini pemikiran orang banyak dipengaruhi oleh doktrin atau ajaran-ajaran agama. Di Eropa banyak dipengaruhi oleh ajaran Kristiani, di Timur Tengah oleh ajaran Agama Islam, di India oleh ajaran Hindu-Budha dan di China oleh ajaran Konfucius/Konghucu. Oleh karena itu ciri yang menonjol corak berpikir orang pada zaman tersebut bersifat Teosentris, artinya tuhan dan ajaran-ajaranya menjadi pusat perhatian dan pemikiran. Konsep tentang hukum juga tidak lepas dari pengaruh ajaran-ajaran agama. Seperti misalnya konsep hukum yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas yang membagi jenis-jenis hukum dari level yang paling tinggi dan abstrak menuju ke yang konkrit dari lex aeterna, lex devina, lex natura, dan lex humana/ lex positiva. Demikian pula Hukum Fiqh yang banyak dikembangkan oleh para Imam di wilayah Timur Tengah seperti Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi dan Imam Syafi’i merupakan jabaran dari ajaran Islam tentang hukum yang sumbernya terdapat dalam al-Quran dan al-Hadits. Di Zaman Pertengahan ini doktrin agama menjadi penentu makna dan ukuran tentang realitas dan kebenaran. Memasuki abad ke-15 di Eropa Barat terjadi perubahan yang sangat fundamental tentang cara berpikir orang tentang realitas. Perubahan Bab 6 289 fundamental itu beregrak dari corak berpikir yang teosentris ke antroposentris, yaitu manusia menjadi pusat segala-galanya. Pandangan Antroposentrisme muncul sebagai pendobrak pandangan teosentrisme, yang beranggapan bahwa kehidupan tidak berpusat pada tuhan, akan tetapi pada manusia. Manusialah yang menjadi penguasa realitas dan bukan tuhan lagi. Manusia adalah penentu kebenaran, sehingga kitab suci atau ajaran-ajaran agama tidak diperlukan lagi. Era ini disebut sebagai Zaman Modern, dengan semangat renaisans. Cita-cita renaisans adalah mengembalikan lagi kedaultan manusia, yang selama berabad-abad telah terampas, dan manusia harus menjadi penguasa alam semesta. Di bidang pemikiran keilmuan terjadi revolusi pemikiran dari Filsafat Ontologi yang menjadi andalan filsafat pada Zaman Kuno dan Pertengahan ke Filsafat Epistemologi. Filsafat Epistemologi inilah yang telah melahirkan teori tentang metodologi yang berhasil melahirkan apa yang disebut metode ilmiah (scientific method). Bermodalkan metode ilmiah ini terbangun ilmu-ilmu modern, termasuk pula Ilmu Hukum Modern, dengan produknya Hukum Modern yang sangat menakankan pada dimensi rasionalitas manusia. Revolusi ilmu pengetahuan yang telah dicapai oleh bangsa barat, ternyata juga menimbulkan masalah-masalah baru. Semangat untuk membebaskan diri dari Tuhan, yang merupakan cita-cita renaisans, ternyata menyebabkan paham agnostisisme terhadap agama, dan pada gilirannya menimbulkan sekularisme dan bahkan atheisme. Di sisi lain revolusi ilmu pengetahuan juga menimbulkan paham bahwa ilmu pengetahuan secara inheren bersifat bebas-nilai. Melalui penyebaran budaya, paham epistemologi barat seperti itu telah tersebar ke seluruh dunia. Melalui pendidikan semangat itu juga tertanam dalam benak para pemikir kita, tak terkecuali di Indonesia. Mereka berpandangan bahwa kemajuan kebudayaan dan kemajuan ilmu pengetahuan hanya dapat terjadi jika kita mampu membebaskan diri dari kungkungan agama dan hal-hal yang tidak rasional. 290 Penutup Dampak epistemologi ilmu-ilmu barat ternyata telah mendegradasikan martabat kemanusiaan (dehumanisasi). Banyak problem manusia modern yang tidak dapat terpecahkan oleh ajaran modernisme itu sendiri. Oleh karena itu di penghujung abad ke-20 terjadi revolusi pemikiran (paradigma) kembali dari yang bercorak antroposentis ke yang bercorak multivers. Oleh sebagian pemikir corak ini menandai lahirnya era baru yang disebut era Postmodern. Muttivers artinya tidak ada sentris (pusat) dan dominasi lagi terhadap penguasaan realitas dan juga patokan kebenaran. Dengan kata lain realitas dan kebenaran itu bersifat plural. Ini ciri khas era Postmodern, yaitu multivers. Menurut Sugiarto (1996), postmodernisme dibedakan dengan postmodernitas, jika postmodernisme lebih menunjuk pada konsep berpikir, sedangkan postmodernitas lebih menunjuk pada situasi dan tata sosial produk teknologi informasi, globalisasi, fragmentasi gaya hidup, konsumerisme yang berlebihan, deregulasi pasar uang dan sarana publik, usangnya negara dan bangsa serta penggalian kembali inspirasiinspirasi tradisi. Postmodern secara singkat sebenarnya ingin menghargai faktor lain seperti tradisi, spiritualitas yang dihilangkan oleh modernisme dengan penampilannya berupa rasionalisme, strukturalisme dan sekularisme. Ciri pemikiran di era postmodern ini adalah pluralitas berpikir dihargai, setiap orang boleh berbicara dengan bebas sesuai pemikirannya. Postmodernisme menolak arogansi dari setiap teori, sebab setiap teori punya tolak pikir masing-masing dan hal itu absah saja. Di Era Postmodern tidak dikenal sentris, dominasi, dan kooptasi, yang dikenal dan dianjurkan adalah pluralisme dan sikap saling menghargai dan memahami (verstehen) atas pluralitas dan perbedaan. Dengan mengaca pada corak zaman Postmodern ini maka setiap orang atau kelompok bebas mengembangkan kreatifitasnya sesuai dengan paradigma berpikir yang dianut dan tanpa harus tunduk pada sebuah dominasi tertentu (sentris) seperti yang terjadi pada zamanzaman sebelumnya (cosmosentris, teosentris dan antroposentris). Di sinilah terdapat peluang untuk mengembangkan Ilmu Hukum Profetik, untuk Bab 6 291 membebaskan diri (liberasi) dari cara berpikir dan berhukum yang selama ini dikuasai oleh dominasi hukum modern dengan coraknya yang antroposentris. Mari kita ber-ijtihad membangun Ilmu Hukum Profetik, semoga bermanfaat. B. Ilmu Hukum Profetik sebagai Tawaran Alternatif Ilmu Hukum Profetik sengaja dihadirkan, disajikan dan diwacanakan sebagai menu sajian tentang gagasan keilmuan alternatif di tengah-tengah jagad para pecinta ilmu, khususnya Ilmu Hukum di era Postmodern ini. Ini dimaksudkan sebagai upaya pencarian dan penemuan kebenaran nilai-nilai hukum (humanisasi/amar ma’ruf), pembebasan (liberasi/nahi munkar) dari cara berhukum yang materialissekular, jauh dari nilai-nilai ketuhanan (transendensi) yang terjadi di Zaman Modern, yang terbukti telah merendahkan peradaban manusia (dehumanisasi). Jika kita telusuri secara lebih seksama, sebenarnya filsafat epistemologi barat yang telah berhasil melahirkan ilmu-ilmu modern (termasuk hukum modern) sebenarnya mengandung cacat bawaan sejak lahirnya. Cacat bawaan ini menyimpan potensi yang membahayakan bagi kelangsungan peradaban manusia dan itu sudah terjadi saat ini. Epistemologi barat telah berdampak pada krisis epistemologi keilmuan yang menyesatkan peradaban manusia selama ini. Cacat bawaan epistemologi tersebut terletak pada cara berpikir ilmuwan modern yang hanya semata-mata bersumber dan mengandalkan pikiran (rasionalisme), baik yang idealis (Platoism-Cartesian) maupun yang empiris (Aristoteleism-Baconian). Sumber pengetahuan yang berupa wahyu yang dibawa oleh para nabi (pengetahuan profetik) tidak mendapatkan tempat, sehingga melahirkan cara berilmu yang berkarakter materialistik, pragmatik, hedonis dan atheistik yang dibungkus dalam naungan Filsafat Positivisme. Dan itu terbukti telah menyebabkan dehumnaisasi, karena manusia berjalan sendiri tanpa petunjuk (huda) yang jelas dan pasti. Penutup 292 Jika kita telusur ke belakang, pemikiran ilmu dan ilmiah modern yang kita kenal dan ikuti saat ini, berdasarkan analisis M. Koenoe, adalah berkat berkembangnya suatu filsafat yang disebut Filsafat Epistemologi. Filsafat ini memusatkan pemikirannya untuk menemukan jawaban atas pertanyaan tentang bagaimana dan sejauh mana validitas kemampuan tahu yang ada pada diri manusia. Di dalam filsafat epistemologi, sasaran pemikirannya yang radikal terarah pada manusia sebagai subjek yang memikir itu sendiri. Di dalam filsafat ini terdapat pemikiran tentang bagaimana kita dapat mengetahui sedemikian rupa sehingga hasilnya dapat diterima menurut ukuran kebenaran yang sesuai dengan pandangan filsafat yang bersangkutan. Hasil pemikiran itu dituangkan ke dalam suatu ajaran menge-tahui yang disebut sebagai ‘ajaran metodologi’. Ajaran ini yang membawa kepada adanya suatu ‘instruksi berpikir’ dalam melakukan kegiatan keilmuan, yang disebut dengan istilah disiplin. Ajaran tentang metodologi, di dalam sejarah pemikiran filsafat di Eropa Barat terdiri dari dua aliran yang secara prinsip berbeda. Perbedaan itu dasar-dasarnya sudah tampak dimulai sejak zaman Yunani Kuno, yang ditunjukkan oleh pendirian Plato (guru) dan Aristoteles (murid) tentang pengetahuan manusia. Menurut Plato, pengetahuan yang ada pada manusia, tidak lain adalah merupakan bayangan, suatu kopi dalam pikiran kita tentang apa yang ada di dalam alam luar kita yaitu alam ‘idee’. Di dalam alam idee yang metafisis itu, segala sesuatu mempunyai wujudnya yang tetap dan abadi. Berbeda dengan Aristoteles, la berpendirian, bahwa pengetahuan kita bersumber dari ‘hal’ yang konkrit yang kita hadapi. Dari pendirian kedua pemikir Yunani Kuno tersebut tampak, bahwa Plato meletakkan dasar mengetahui yang bersifat metafisis, sedangkan Aristoteles meletakkan dasar mengetahui yang realistis konkrit atau empiris. Perbedaan pendirian antara guru-murid tersebut dalam dasarnya merupakan perbedaan dalam filsafat yang dianut masing-masing mengenai hakikat dari suatu realitas. Bab 6 293 Perbedaan pendirian antara Plato dan Aristoteles yang pada dasarnya merupakan perbedaan dalam ontologinya, pada kurun waktu berikutnya pusat pemikiran filsafat di Eropa Barat mulai bergeser, yaitu dari pandangan tentang ontologi, (artinya filsafat tentang hakikat kebenaran dari objek yang menjadi pokok pemikiran) menjadi pemikiran epistemologi, (yaitu pemikiran tentang subjek yang memikir itu sendiri). Di dalam pemikiran epistemologi, yang sentral menjadi sasaran pemikiran filsafat adalah manusia sebagai subyek yang memikir. Dalam hal ini yang ditanyakan ialah bagaimana manusia sampai dapat mengetahui segala sesuatu? Dalam menghadapi pertanyaan itu filsafat epistemologi di daratan Eropa Barat memberi jawaban, bahwa itu adalah karena pada diri manusia ada ‘pikiran’. Sekali lagi ‘pikiran’. Itu yang yang merupakan alat dan sekaligus sumber dari pengetahuan manu-sia, dan pikiran itu adalah sesuatu yang metafisis. Dari itu epistemologi yang dianut oleh para pemikir di daratan Eropa Barat adalah epistemologi yang metafisis. Aliran yang demikian ini adalah aliran dalam rangka pendirian Plato. Lain lagi epistemologi yang dianut oleh kalangan pemikir di Inggris. Kalangan itu mengikuti aliran Aristoteles yang realistis. Pemikir epistemologi Inggris tergolong pemikir yang mengikuti dan berpegangan kepada epistemologi yang empiris. Perbedaan dasar-dasar dalam epistemologinya itu membawa pula perbedaan dalam cara berpikir ilmiahnya. Di daratan Eropa Barat diutamakan segi metafisisnya. Pengutamaan pandangan metafisis itu menentukan pendekatan di dalam ajaran berilmu pengetahuan. Atas dasar pandangan itu, pendekatan keilmuan di daratan Eropa Barat menganut pendekatan yang bersifat deduktif-spekulatif. Di Inggris diutamakan segi empirisnya, dengan mengutamakan pendekatan yang kausal-empiris-analitis (induktif). Perbedaan mengenai aliran epistemologi antara daratan Eropa Barat dan Inggris, tidak saja membawa perbedaan dalam tekanan perhatian dalam berilmu beserta jalan pendekatan berilmu. Perbedaan tersebut juga membawa perbedaan dalam hal tujuan dalam berilmu. 294 Penutup Di daratan Eropa Barat, tujuan berilmu ialah seperti yang sejak abad pertengahan dikemukakan oleh Thomas van Aquino yaitu dalam rangka memenuhi panggilan jiwa manusia yang selalu ingin mengetahui, atau dalam rumusan bahasa Latin ‘desiderium sciendi’. Di Inggris, seperti dikemukakan oleh oleh Francis Bacon, tujuannya didasarkan kepada pandangan bahwa ‘knowledge is power’, pengetahuan adalah kekuasaan. Perbedaan pendirian mengenai tujuan berilmu, menunjukkan pula perbedaan filsafat hidup yang melatar belakanginya. Di daratan Eropa Barat, filsafat hidup yang menjadi latar belakangnya ialah ‘penyempurnaan manusia’, sedangkan di Inggris yang melatar belakanginya adalah faham hedonisme, atau eudemonisme yaitu yang jiwanya sebagaimana dirumuskan Adam Smith yaitu untuk menjelmakan ‘the greatest happiness for the greatest number’. Kemudian filsafat ini di Amerika Serikat dikembangkan menjadi filsafat pragmatisme, yang di dalam kejiwaannya, seperti yang dirumuskan secara ringkas oleh William James yaitu untuk memenuhi keinginan the satisfaction of human wants. Baik di daratan Eropa Barat, maupun di Inggris, sekalipun antara keduanya dalam hal pandangan epistemologinya ada prinsip-prinsip yang berbeda, namun antara keduanya ada juga kesamaannya. Antara kedua aliran itu dalam hal semangat yang mendasari filsafat epistemologinya sama-sama hanya mengandalkan kepada kemampuan yang ada pada diri manusia saja. Di daratan Eropa Barat kekuatan tahu itu berkat adanya pikiran manusia saja, cogito ergo sum, saya berpikir, karena itu saya ada, kata Rene Descartes. Sementara itu di Inggris ditekankan kepada pengalaman, experience is the best teacher, pengalaman adalah guru yang terbaik. Selain itu kedua-duanya di dalam epistemologinya juga menunjukkan kesamaannya yaitu bahwa filsafat epistemologinya itu sama sekali terlepas dari faham Ketuhanan yang diajarkan oleh gereja. Di dalam pengembangan filsafat Hukum, hal ini tampak jelas dalam ucapan Hugo Grotius yang bunyinya ‘etiamsi daremus non esse Deum, artinya di dalam memikirkan Hukum Kodrat, ‘anggaplah seolah-olah Tuhan itu tidak ada.’ Bab 6 295 Eropa Barat, dengan berpedoman kepada filsafat epistemologi yang hanya mengandalkan pikiran saja, atau Inggris yang hanya mengandalkan pengalaman saja, mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menanggalkan sama sekali faham Ketuhanan yang diajarkan gereja dalam abad-abad sebelumnya. Abad ke XVIII dapat dikatakan bahwa terutama bagi daratan Eropa Barat merupakan abad pikiran, atau rasionalisme. Pengembangan ilmu pengetahuan yang dibangun dan dikembangkan semata-mata dengan mengandalkan pada kekuatan mengetahui manusia yaitu pikiran saja atau empiri saja, ternyata pada permulaan abad ke XIX, mulai meluntur. Perkembangan selanjutnya dari filsafat yang demikian mulai mendapat tantangan. Di daratan Eropa Barat tantangan tersebut terutama dibawa oleh perkembangan aliran romantik dan filsafat kritis. Dengan itu timbul ketidak puasan terhadap pengembangan filsafat dan ilmu pengetahuan yang mengutamakan segi rasionilnya saja meninggalkan segi-segi ethik, aesthetika, dan lain-lain nilai-nilai kejiwaan yang tidak masuk di dalam alam akal atau empiri. Memasuki abad ke XX, terjadi lagi suatu pembaharuan dalam filsafat di daratan Eropa Barat. Filsafat tersebut tidak mengikuti filsafat objektip (filsafat ontologi), juga tidak mengikuti filsafat subjektip (filsafat epistemologi). Aliran baru ini mengajukan pandangannya sendiri dimana subjek-objek disatukan. Filsafat ini mengajarkan bahwa alam nyata harus dibedakan dari keadaannya atau existensinya. Existensi alam nyata ini adalah tidak tetap. Itu tunduk kepada perubahan-perubahan yang terus menerus. Perubahan itu terjadi bilamana keadaan dari alam nyata itu mencapai suatu garis batas dari keadaannya. Di dalam istilah filsafat di Jerman garis batas keadaan dari sesuatu itu disebut dengan istilah grenzsituation atau disebut existensialisme. Perkembangan selanjutnya dari Filsafat Barat akhir-akhir ini adalah lahirnya filsafat Postmodernisme. Filsafat ini bersifat irrasionil dan dalam ajarannya filsafat ini menentang foundationalisme, essentialisme dan realisme. Perkembangan pemikiran filsafat ini dikemukakan dengan tujuan untuk memahami garis besar perkembangan Filsafat Barat terutama 296 Penutup filsafat epistemologi sebagai pencetus dan pemberi dasar lahirnya ilmu dan pemikiran ilmiah yang hingga kini kita jumpai dan ikuti. Sudah barang tentu perkembangan filsafat selanjutnya seperti existensialisme dan post modernisme, juga mempengaruhi dan menentukan keilmuan dan pemikiran ilmiah modern dewasa ini. Pangkal dasar yang dulu diletakkan oleh Plato yaitu alam idee dan Aristoteles yaitu pada halnya yang konkrit, kini telah berkembang sedemikian rupa sehingga pangkal dasar untuk mengetahui menjadi bermacam-macam jenisnya. Hal itu dapat ditunjukkan kepada pertanyaan-pertanyaan yang timbul tentang dari mana mulai mengetahui itu. Tetapi bagaimanapun, pengembangan ilmu dan keilmiahan modern dalam abad ke XX ini tidak terlepas dari pengaruh semangat dan kejiwaan yang didasari oleh filsafat yang menjiwai abad ke XVIII yang masih hidup dalam awal abad XIX. Dasar-dasar dan benihbenih pemikiran ilmu dan keilmiahan yang diajarkan oleh filsafat epistemologi pada masa itu, tetap berperan penting karena pada masa itu lahirnya apa yang dinamakan ‘teori besar’ dari ilmu pengetahun yang sampai kini tetap kita kenal dan menjadi perhatian. Pemeliharaan keilmuan dan keilmiahan tetap mengandalkan terutama kepada kekuatan ‘pikiran’ atau ‘empiri’ manusia saja dengan meninggalkan faham ‘Ketuhanan’. Jiwa yang demikian, ilmu dan keilmiahan Eropa Barat memasuki abad ke XX, menyeret dunia di dalam pemeliharaan dan pengembangan ilmu dan keilmiahannya sampai kini. Selain itu, di dalam abad ke XX ini, kedua macam filsafat yang kuat dianut di Eropa yaitu filsafat yang metafisis yang begitu kuat hidup di daratan Eropa Barat, maupun filsafat yang empiris yang berkembang di Inggris dan Amerika Serikat, menunjukkan bahwa filsafat empiris beserta sistim pemikiran yang kausaal-empiris-analitis pada akhir-akhir ini yang menunjukkan pengaruhnya yang lebih populer dan dominan. Filsafat empirisme, tidak saja mengajarkan bagaimana berpengetahuan, tetapi filsafat itu juga mengandung filsafat hidup pula Bab 6 297 yang dasarnya ialah empiris. Filsafat hidup atas dasar empirisme ini, yaitu filsafat hedonisme, pada bagian akhir abad ke XIX, di Amerika Serikat berkembang menjadi filsafat pragmatisme dengan dasar-dasar yang materialistis. Filsafat hidup itu kini yang menguasai kehidupan kemanusiaan dengan kuat dalam skala global. Filsafat itu yang kini menjadi jiwa dan landasan dari apa yang kini secara populer disebut globalisasi. Sejarah peradaban Eropa Barat menunjukkan bahwa sampai abad ke XII Eropa Barat berada di dalam abad kegelapan (the dark ages). Kegelapan tentang semesta kenyataan ini dihadapi filsafat barat dengan hanya mengandalkan kepada kemampuan daya pikir manusia. Hal itu dilakukan dengan rintisan untuk memikirkannya secara radikal dan logis sistematis yang disebut dengan jalan filsafat. Dalam kegiatan memikirkan semesta kenyataan sebagai teka-teki, diperoleh jawaban yang sifatnya berupa tebakan terhadap semesta kenyataan dengan mengandalkan pikiran. Dalam sejarah Islam, zaman sebelum datangnya Islam juga disebut sebagai zaman kegelapan atau jahiliah. Artinya bahwa semesta kenyataan ini pada masa itu adalah suatu misteri yang mengandung teka-teki yang tidak ada yang dapat memberikan penjelasan tentang ‘clara et distincta perceptio’nya. Dengan datangnya Islam yang diajarkan oleh Rasulullah, kegelapan tersebut diungkap. Untuk mengungkap itu pertama-tama dituntut untuk memiliki alat yang dapat membawa terang terlebih dahulu keadaan gelap itu. Di dalam keadaan gelap, bilamana ingin tahu tentang sesuatu mengenai apa dan bagaimananya, diajarkan bahwa sebelumnya orang harus menggunakan suatu alat yang dapat membuat keadaan gelap itu berada dalam keadaan yang terang terlebih dahulu. Di dalam permulaan surat al-Baqarah, alat yang dapat membawa keadaan terang itu ialah ‘iman’ kepada Yang Maha Pencipta semesta kenyataan ini. Dengan iman orang akan dibawa kepada pengakuan bahwa semesta kenyataan ini ada yang menciptakannya. Selanjutnya bahwa ciptaanya itu ada dan berjalan menurut ketentuan dan rancanganNya sebagaimana dikehendaki olehNya. 298 Penutup Dengan itu semesta kenyataan ini hanya dapat diketahui dan dimengerti, bila tentang itu diperoleh penjelasan dari Yang Maha Mencipta itu. Penjelasan itu hanya dapat diterima oleh manusia bila dia pertamatama beriman kepadaNya sebagai Yang Maha Pencipta. Pengetahuan atas dasar iman, adalah pengetahuan yang diperoleh bukan atas dasar menerka dalam kegelapan, tetapi diperoleh dan didasarkan pada pemberitahuan dari Penciptanya sendiri yaitu beriman kepada wahyu (pemberitaan Tuhan). Dengan dasar itu selanjutnya oleh al-Qur’an ditunjukkan syaratsyarat lain yang harus dipenuhi seseorang yang sudah berada di dalam keadaan yang terang jiwanya untuk mengembangkan pengetahuannya selanjutnya. Syarat-syarat itu, seperti tertera di dalam permulaan surat al-Baqarah, bila dikemukakan secara bebas adalah sebagai berikut: a. Bahwa dalam segala keadaan, seorang di dalam menjalani keadaannya, akan selalu tetap memerlukan petunjukNya untuk dapat selalu berada di dalam jalan yang lurus yang ditentukan olehNya, b. Bahwa dalam menjalani ke-ada-annya, orang harus menjauhkan diri dari watak tamak yang materialistis, c. Bahwa semesta kenyataan ini olehNya ditentukan berada dalam suatu proses yang tiada hentinya menuju kepada bentuknya yang terakhir sebagaimana yang dikehendakiNya. Prinsip-prinsip tersebut sebagai syarat dan dasar bagi manusia untuk memahami semesta kenyataan yang diperintahkan Allah yaitu selalu menggunakan alat-alat kemampuan mengetahui dan memahami berupa wahyu, fikiran, akal dan hati yang ada pada manusia. Inilah landasan utama Epistemologi Ilmu Hukum Profetik, bedanya yang tidak profetik. Landasan epistemologi ini membutuhkan penggalian, pemikiran dan pengembangan lebih lanjut untuk membangun sosok yang lebih jelas tentang Ilmu Hukum Profetik. Uraian yang terdapat pada buku ini, dari awal sampai akhir sebatas membicarakan dari segi landasan kefilsafatanya dan belum sampai pada struktur keilmuannya. Untuk sampai ke struktur keilmuanya, kita Bab 6 299 setidak-tidaknya membutuhkan 4 (empat) perangkat, yaitu Filsafat Profetik, Filsafat Ilmu Profetik, Filsafat Ilmu Hukum Profetik dan Ilmu Hukum Profetik. Untuk perangkat pertama dan kedua sudah dilakukan oleh Kuntowijoyo dan Heddy Shri Ahimsa-Putra dengan segala kelebihan dan kekurangan. Untuk perangkat yang ketiga buku ini jawabannya dan untuk perangkat keempat masih perlu dicari dan diupayakan realisasinya. Sungguh upaya dan pencarian yang panjang, semoga Allah selalu memberi petunjuk, tambahan ilmu dan intuisi yang lebih baik (Robbi zidni ‘ilman warzukni fahman). Amien. 300 Penutup DAFTAR PUSTAKA Abdullah, M. Amin. 2006. Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. _______, 1998. “Preliminary Remarks on the Philosophy of Islamic Religious Science”, Al-Jami’ah, No. 61, TH., 1998. Abu-Rabi’, Ibrahim M. and Ian Markham (Ed.). 2002. 11 September: Religious perspectives on the causes and consequences ,Oxford: Oneworld Publications. Adonis. 2002. al-Tsabit wa al-Mutahawwil: Bahts fi al-ibda’ wa al-itba’ ‘inda al-arab, London: Dar al-Saqi. Adz-Dzakiey, Hamdani Bakran. 2008. Psikologi Kenabian, Prophetic Psychology Menghidupkan Potensi dan Kepribadian Kenabian dalam Diri. Ctk ketiga. ogyakarta: Al-Manar. Adiprasetya, Joas. 2002. Mencari dasar bersama: etik global dalam kajian postmodernisme dan pliuralisme agama, Jakarta: BPK Gunung Mulia. Al-Jabiry, Mohammad Abid. 2002. Madkhal ila falsafah al-ulum: alAqlaniyyah al-mu’asirah wa tathawwur al-fikr al-ilmy, Beirut: Markaz Dirasaat al-Wihadah al-Arabiyyah, Cetakan ke -5. Ahimsa-Putra, Heddy Shri, 2011. “Paradigma Profetik sebuah Konsepsi”, Makalah disampaikan dalam Diskusi Pengembangan Ilmu Profetik 2011,diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum - UII, di Yogyakarta, 18 Nopember 2011. _______, 2008. Paradigma dan Revolusi Ilmu Dalam Antropologi Budaya: Sketsa Beberapa Episode. Pidato Pengukuhan Guru Besar. Yogyakarta; Universitas Gadjah Mada. _______, 2009. “Paradigma Ilmu Sosial-Budaya: Sebuah Pandangan”. Makalah ceramah. 302 Daftar Pustaka Anonim. 2002. Laporan Penyelenggaraan Sarasehan Ilmu-ilmu Profetik, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. An-Na’im, Abdullahi Ahmed. 1996. Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law, New York: Syracuse University Press. Arto, Ahmad Mukti. 2006. Mencari Keadilan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Auda, Jasser, Maqasiid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, London dan Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008. Anonim. Lajnah Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Nahdhatul Ulama DIY, Seminar Nasional “Teologi Pembangunan”. Kaliurang 25-26 Juni 1988. Baderin, Mashood A. 2003. International Human Right and Islamic Law, Oxford and New York: Oxford University Press. Banawiratma, J.B., Zainal Abidin Bagir, etc. 2010. Dialog Antarumat Beragama: Gagasan dan Praktik di Indonesia, Jakarta: Mizan Publika. Bartol dan Bartol. 1994. Psychology and Law. California: Brooks/Cole Publishing Company. Barbour, Ian G. l966. Issues in Religion and Science, New York: Harper Torchbooks. Boullata, Issa J. (Ed.). l992. An Anthology of Islamic Studies, Canada: McGill Indonesia IAIN Development Project. Burgoon, J. Buller D, Woodall G. 1989. Nonverbal Communication. New York: Harper and Row Publishers. Brigham, J.C. 1991. Social Psycholoy. New York : Harper Collins Publisher. Black, Donald. 1976. The Behavior of Law. New York: Pegassus. Cuff, E.C. dan G.C.F.Payne (eds.). 1979. Perspectives in Sociology. London: George Allen & Unwin. Darmodiharjo, D. & Shidarta. 1996. Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo. El-Ansary, Waleed dab David K. Linnan (Ed.). 2010. Muslim and Christian Understanding: “A Theory and Application of “A Common Word”, New York: Palgrave Macmillan. El-Fadl, Khaled Abou. 2001. Speaking in God’s Name: Islamic Law, Authority, and Women, Oxford: Oneworld. Friedman, L.M. 1977. Law and Society : An Introduction, New Jersey: Prentice Hall. Daftar Pustaka 303 _______, 1975. The Legal System : A Social Science Perspektive, New York : Russel Sage Fondation. _______, 1986. American Law, New York: W.W.Norton & Co. Fred N. Kerlinger. 1973. Foundations of Behavioral Research, (second edition). Holt, Rinehart and Winston. London. Fuady, Munir. 2003. Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti. Gunawan, Ahmad dan Ramadhan, Muammar (Penyunting). 2006. Menggagas Hukum Progressif Indonesia. Yogyakarta: Pusataka Pelajar. Gardon, Scott. 1991. The History and Philosophy of Social Science. London: Toutdge. Hammersley, Martyn. 1995. The Politics of Social Research. London: Sage. Hasan, Ahmad. 1985. IJMA. Bandung, Penerbit Pustaka. Hickling, R.H. 1996. Major Legal Systems. Centre for Southerns Asian Law Faculty of Law, Northern Teritorry. Huntington, Samuel, 2002. The Clash Civilizations and the Remaking of World Order. London. WC2B. An Imprint of Simon Suchter UK.. Http://www. hukumonline.com, Cari Hakim Jujur Lewat Eksaminasi Putusannya, diakses tanggal 18 Februari 2007. Http://erabaru.net/opini/65-opini/10099-menegakkan-keadilanjangan-sekedar- menegakkan-hukum, diakses tanggal 20 April 2010. Http://www.sunan-ampel.ac.id/publicactivity/detail.php?id=28, diakses tanggal 20 April 2010. Http://bambang.staff.uii.ac.id/index.php, diakses tangggal 20 April 2010. Ian G. Barbour. 2000. When Science Meets Religions. Enemies, Strangers, or Patner. Harper Collins Publisher Inc. Inkeles, A. 1964. What is Sociology?. Englewood Cliffs, N.J.: PrenticeHall. Koesnoe, M. 1981. “Kritik Terhadap Ilmu Hukum”. Makalah Ceramah di Hadapan Para Dosen dan Mahsaiswa Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 3-4 Pebruari 1981. Kuhn, T. 1970. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: The University of Chicago Press. Second Edition, Enlarged. Kuhn, Thomas, Habermas, Jurgen. 1997. Between Facta and Norms: Contribution to a Discourse Theory of Law and Democracy (translated by William Rehg). Polity Press Oxford, UK. 304 Daftar Pustaka Kuntowijoyo, 2006. Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika. Yogyakarta: Tiara Wacana. Kaelan, 201. Implementasi Nilai-Nilai pancasila dalam menegakan Konstitusionalitas Indonesia. Jakarta. Mahkamah Konstitusi RI dengaan Universitas Gadjah Mada.. Kompas, 26 Nopember 1998. Kusumaatmadja, 1986. Muchtar, Fungsi dan Perkembangan hukum dalam Pembangunan Nasional, Lembaga Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, diedarkan oleh Penerbit Bina Cipta, Bandung Macaulay, Stewart., 1963. Non Contractual Relation in Business. American Sociological Review. Kuhn, Thomas, 1962. The Structure of Scientific Revolutions, Chicago. University of Chicago Press. Le Bon, Gustav. 1974. The World of Islamic Civilization, terj. oleh David Macrae, Todor Publishing Company Luhman, Niklas. 1985. A Sociological Theory of Law. London : Routledge & Kegan Paul. Luthan, Salman, 2011. “Gagasan Ilmu Hukum Profetik”. Makalah disampaikan dalam Diskusi Pengembangan Ilmu Profetik 2011,diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum - UII, di Yogyakarta, 18 Nopember 2011. Luthan, Salman & Triyanta, Agus. 1997. “Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparat Keadilan”. Jurnal Hukum FH-UII. No. 9. Vol. 4-1997. Lemek, Jeremies, 2007. Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakkan Hukum di Indonesia, Galang Press, Yogyakarta. Martin, Richard C., (Ed.). l985. Approaches to Islam in Religious Studies, Arizona: The University of Arizona Press. Munitz, Milton K., 1981. Contemporary Analytic Philosophy, New York: MacMillan Publishing CO,. Inc. Mahfud, MD, Moh. 1997. “Politik Hukum untuk Independensi Lembaga Peradilan”. Jurnal Hukum FH-UII. No. 9. Vol. 4-1997. Mauwissen. 1994. “Pengembanan Hukum “ PRO JUSTITIA Tahun XII Nomor 1 Januari 1994. Mulyatno. 1982. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yogyakarta: Bina Aksara. Madjid, Nurcholis, 2005. Islam Doktrin dan Peradaban, “Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan”. Jakarta: Penerbit Paramadina. Daftar Pustaka 305 _______, 1993. Islam, Kemodernan dan Ke-Indonesiaan, Bandung: Mizan. Ma’arif, Syafi’i. 1993. Peta Bumi Intelektual Muslim di Indonesia, Bandung: Mizan. Masterman, M. 1970. “The Nature of a Paradigm” dalam Criticism and the Growth of Knowledge, I. Lakatos dan A.Musgrave (eds.). Cambridge: Cambridge University Press. Muqodas, Busyro, 2006. “Peran Komisi Yudisial RI dalam Pemberantasan Mafia Peradilan di Indonesia”. Makalah dalam Diskusi Publik Komisi Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Jawa Tengah, 1 Pebruari 2006. Mudzakkir, “Urgensi dan Relevansi Eksaminasi Publik”. Makalah dalam diskusi panel yang diselenggarakan oleh Departemen Acara FH UII, Pusdiklat Laboratorium UII, ICW. Mertokusumo, Sudikno, 2004. Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta, Liberty. _______, 1997. “Sistem Peradilan di Indonesia”. Jurnal Hukum FH-UII. No.9. Vol.4-1997 Merton, R.K., 1968. Social Theory and Scoial Structure. New York: The Free Press. Nagel, E. 1961. The Structure of Science: Problems in the Logic of Scientific Explanation London: Routledge and Kegan Paul. Program Studi Agama dan Lintas Budaya (Center for Religious and Crosscultural Studies/CRCS, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia, 2009. Parsons, Talcott. The Social System: The Major Exposition of the Author’s Conceptual Scheme for the Analisis of the Dinamics of the Social System. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2263.K/Pdt/1991. Qodir, C.A. 1991. Filsafat dan Ilmu Pengetahuan dalam Islam. Jakarta: Yayasan Obor. Rahman, Fazlur, Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition, Chicago: The University of Chicago Press, l982. Ramadan, Tariq, Western Muslims and the Future of Islam, New York: Oxford University Press, 2004. Rolston, Holmes III, Science and Religion: A Critical Survey, New York: Random House, l987. Reynolds, A. 1980. A Primer in Theory Construction. Ratoosh, P. 1973. “Sense and Sensation”. Encyclopedia Americana vol.24: 559-561. 306 Daftar Pustaka Ritzer, George and Doglas, Goodman, Modern Sociological Theory. (Six Edition), McGraw-Hill. Mariland, USA. 2003. A.15. Rahayu, Yusti Probowati, “Putusan Hakim Pada Perkara Pidana: Kajian Psikologis”. Buletin Psikologi Fakultas Psikologi UGM tahun III Nomor 1 Agustus 1995 Rawls, John, Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, Pusaka Pelajar, Yogyakarta, 2006. Rahardjo, Satjipto, “Pendekatan Holistik terhadap Hukum”. Jurnal Hukum Progresif Volume: 1 Nomor 2/ Oktober 2005. Rahardjo, Satjipto. Tanpa tahun. Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Bandung : Sinar Baru. _______, 2006. “Pemberantasan Korupsi Progresif”. Makalah disampaikan Pada diskusi Peran Komisi Yudisial dalam Pemberantasan Mafia Peradilan di Indonesia. FH Unissula / Kp2KKN Semarang 1 Pebruari. _______, 1998. “Keluasan Reformasi Hukum”, Kompas, 8 Mei. Sidharta, Bernard Arief, 1999. Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, sebuah Penelitian tentang Fondasi kefilsafatan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia. Bandung: Mandar Maju. Stone, Julius, 1969. Law and Social Sciences. Minneapolis. University of Minnesota Press. Saeed, Abdullah, 2006. Interpreting the Qur’an: Towards a contemporary approach, New York NY: Routledge. Saeed, Abdullah, 2006. Islamic Thought: An Introduction, London and New York: Routledge. Safi, Omit (Ed.), 2003. Progressive Muslims: On Justice, Gender and Pluralism, Oxford: Oneworld Publications. Saridjo, Marwan (Ed), 200. .Mereka Bicara Pendidikan Islam: Sebuah Bunga Rampai, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Shahrur, Mohammad, 2000. Nahw usul al-jadidah li al-fiqh al-Islamy: Fiqh al-mar’ah, Damaskus: al-Ahali. Sumartana, Th., dkk. 2005. Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan kedua. Sardar, Ziauddin (Editor), 1989. An Early Crescent: The Future of Knowwledge and the Enironment in Islam. London and New York. Mansel. Sutiyoso, Bambang, 2009. Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan, Jogjakarta, UII Press. Daftar Pustaka 307 Syah, Mudakir Iskandar. 1985. Hukum Dan Keadilan, Grafindo Utama, Jakarta. Siregar, Bismar. 1995. Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan, Jakarta, Gema Insani Press. Widoyoko, Danang et. al. Menyingkap Tabir Mafia Peradilan, Jakarta, ICW, Soegangga, I.G.N., 1994. Pengantar Hukum Adat. Semarang: Badan Penerbit Undip; Smith.V.L.1991. “Impact of Pretrial Instruction on Juror’s Information Prossesing and Decision Making”. Journal of Applied Psycology. Suryabrata, S.1993. Psikologi Kepribadian. Ctk. Keenam. Jakarta: Rajawali Press. Sarwono, Sarlito W. 1995. Teori-Teori Psikologi Sosial. Saduran. Jakarta: PT Raja Grafindo. Sugiharto, Bambang. 1996. Postmodernisme - Tantangan bagi Filsafat, Yogyakarta: Kanisius. Suriasumantri, Jujun S. 1994. Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Twinning, William. 2000. Globalization and Legal Theory. Santos dan Haack, and Calvino, Globalization, Post-modernism, and pluralism. Butterworth. London. Thontowi, Jawahir. “Pengembangan Ilmu Hukum Berbasis Religious Science: Dekonstruksi Filosofis Pemikiran Hukum Postivistik”. Makalah disampaikan dalam Kuliah Tamu di Paskasarjana Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang. diselenggarakan 13 Agustus 2011. _______, 2010. Menuju Ilmu Hukum Berkeadilan. Disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar. Diselenggarakan 20 Desember di dalam Sidang Senat Terbuka Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Varia Peradilan, 1996. No.129. Wilk, K, 1950. The Legal Philosophies of Laks, Radbruch, and Dabin. Cambridge. Massachusetts. Harvard university Press. Wignjosoebroto, Soetandyo. 2013. Hukum Konsep dan Metode. Malang: Setara Press. _______, 2002. Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. Jakarta: Huma. _______, 2000. “Permasalahan Paradigma dalam Ilmu Hukum”. Jurnal Ilmu Sosial Transformatif , Edisi 6- Tahun II 2000. 308 Daftar Pustaka Wilson, Edward O. 1998. Consilience, The Unity of Knowledge. Alfreda Knoff New York. www.jasserauda.net www.maqasid.net.