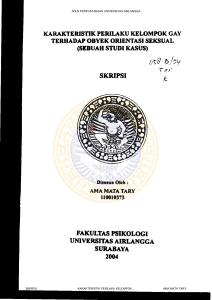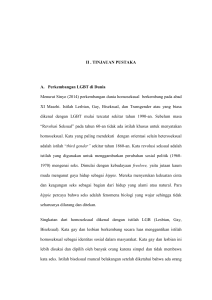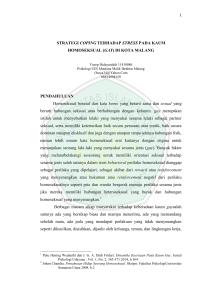Yang “Personal” dan Homophobia Oleh: Wisnu
advertisement
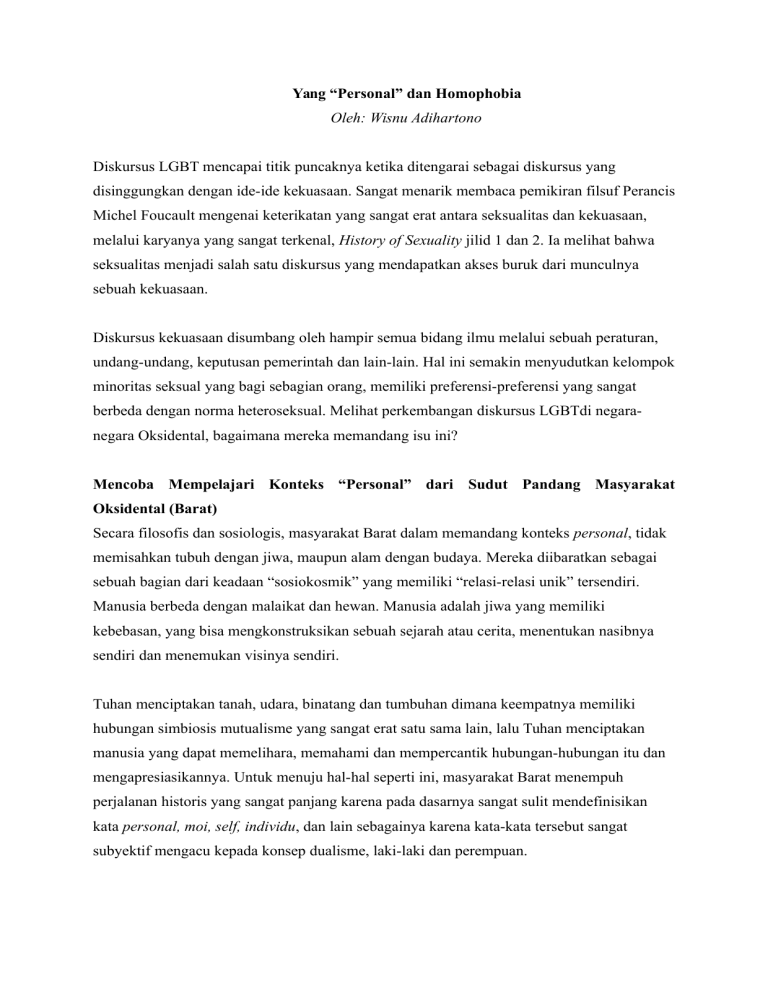
Yang “Personal” dan Homophobia Oleh: Wisnu Adihartono Diskursus LGBT mencapai titik puncaknya ketika ditengarai sebagai diskursus yang disinggungkan dengan ide-ide kekuasaan. Sangat menarik membaca pemikiran filsuf Perancis Michel Foucault mengenai keterikatan yang sangat erat antara seksualitas dan kekuasaan, melalui karyanya yang sangat terkenal, History of Sexuality jilid 1 dan 2. Ia melihat bahwa seksualitas menjadi salah satu diskursus yang mendapatkan akses buruk dari munculnya sebuah kekuasaan. Diskursus kekuasaan disumbang oleh hampir semua bidang ilmu melalui sebuah peraturan, undang-undang, keputusan pemerintah dan lain-lain. Hal ini semakin menyudutkan kelompok minoritas seksual yang bagi sebagian orang, memiliki preferensi-preferensi yang sangat berbeda dengan norma heteroseksual. Melihat perkembangan diskursus LGBTdi negaranegara Oksidental, bagaimana mereka memandang isu ini? Mencoba Mempelajari Konteks “Personal” dari Sudut Pandang Masyarakat Oksidental (Barat) Secara filosofis dan sosiologis, masyarakat Barat dalam memandang konteks personal, tidak memisahkan tubuh dengan jiwa, maupun alam dengan budaya. Mereka diibaratkan sebagai sebuah bagian dari keadaan “sosiokosmik” yang memiliki “relasi-relasi unik” tersendiri. Manusia berbeda dengan malaikat dan hewan. Manusia adalah jiwa yang memiliki kebebasan, yang bisa mengkonstruksikan sebuah sejarah atau cerita, menentukan nasibnya sendiri dan menemukan visinya sendiri. Tuhan menciptakan tanah, udara, binatang dan tumbuhan dimana keempatnya memiliki hubungan simbiosis mutualisme yang sangat erat satu sama lain, lalu Tuhan menciptakan manusia yang dapat memelihara, memahami dan mempercantik hubungan-hubungan itu dan mengapresiasikannya. Untuk menuju hal-hal seperti ini, masyarakat Barat menempuh perjalanan historis yang sangat panjang karena pada dasarnya sangat sulit mendefinisikan kata personal, moi, self, individu, dan lain sebagainya karena kata-kata tersebut sangat subyektif mengacu kepada konsep dualisme, laki-laki dan perempuan. Pada abad ke 3 sebelum masehi, personal tidak ada di dalam literatur-literatur teologi. Hanya Tuhan lah yang memiliki hipostas yang tercermin dari Trinitasnya, yaitu Bapa, Gembalagembala Bapa dan Roh Kudus. Namun, pandangan ini berubah setelah abad ke 4 sebelum masehi dengan munculnya personal yang juga memiliki hipostas. Personal memiliki to be (ontique atau ousia) yang terintegrasi secara total dan dimanifestasikan dalam sebuah esensi kedirian. Dalam konteks teologi Latin, Tuhan menciptakan personal bukan sebagai sebuah atribut yang ada dalam diri personal itu sendiri, tetapi justru personal-lah yang memiliki atribut-atribut tersebut, dengan kata lain personal memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya secara internal dan eksternal yang pada akhirnya memiliki sebuah eksistensi. Konteks ini menginspirasi John Locke untuk mendefinisikan personal sebagai yang memiliki diri atau self (internal dan subjektif) sekaligus memiliki tubuh (eksternal dan objektif). Alam pikiran Barat yang demikian tentunya telah menempuh tempaan sejarah yang sangat panjang. Ketika mereka berbicara mengenai “menjadi laki-laki, perempuan, gay, lesbian, transjender, dan sejenisnya”, maka mereka berbicara tentang “menjadi individu yang memiliki eksistensi internal dan eksternal”.“Menjadi individu yang memiliki eksistensi secara internal” dimaknai sebagai personal yang memiliki unsur self, atau dengan kata lain, individu yang “berbicara” hanya pada dirinya sendiri. Sedangkan “menjadi individu yang memiliki eksistensi eksternal” dimaknai sebagai individu yang “berbicara” dengan orang lain. Dengan demikian, ada dua hal penting yang melatarbelakanginya, yaitu personal sebagai yang berbicara dan personal yang memiliki eksistensi (hypostas). Personal secara tata bahasa adalah “orang yang berbicara dengan dirinya sendiri, berbicara dengan orang lain, dan bertindak untuk dirinya sendiri dan orang lain untuk sebuah aksi”. Contoh yang dapat saya berikan disini berkenaan dengan bagaimana mereka memaknai LGBT adalah ketika mereka tidak asal menghakimi eksistensi mereka. Tentu saja tidak semua masyarakat Barat setuju dengan eksistensi LGBT, akan tetapi sebagian besar dari mereka, sudah paham bagaimana cara memaknai personal dimana mereka harus menghargai self mereka sendiri sebagai manusia yang hidup di tengah masyarakat yang beraneka ragam dan bagaimana mereka memaknai personal yang “harus berbicara” dengan orang lain tanpa memandang orientasi seksual. Pemikiran Kelompok Borjuis dalam Memaknai “Seksualitas Pinggiran” Namun, terlepas dari konteks personal di masyarakat Barat yang memiliki sejarah yang begitu panjang dan kompleks, membicarakan diskursus homoseksualitas tentunya tidak akan terlepas begitu saja dari pengaruh-pengaruh sosial dan budaya yang telah terkonstruksi sedemikian rupa di dalam kepala setiap manusia. Salah satu feminis Prancis, Françoise Héritier mengatakan bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan ada dimana-mana. Laki-laki selalu mendominasi perempuan, dan konsep ini melahirkan sebuah sistem hirarki , yaitu sistem androsentrik (androcetrique) dimana laki-laki yang menjadi pusatnya. Mengacu kepada pemikiran diatas, seorang filsuf Perancis Michel Foucault menegaskan bahwa homoseksualitas merupakan kategori yang terkonstruksi. Akibat yang dihasilkan dari konstruksi tersebut adalah homoseksualitas dipatologisasi (pathologised) sebagai sesuatu yang menyimpang. Menurut Foucault, tidak ada kekuasaan tanpa adanya sebuah resistensi yang sengaja dibentuk menjadi sebuah kebenaran. Pandangannya didasari pada perilaku kelompok borjuis di abad ke 19 yang membedakan tubuhnya sendiri atas tubuh kelompok orang miskin, yang pada saat itu mereka jadikan sebagai budak. Kelompok borjuis memberikan pemahaman-pemahamannya sendiri terhadap tubuh dan reproduksi, yang lamakelamaan menjadi sebuah “strategi” dan “kebenaran” untuk menghakimi seksualitas pinggiran (sexualités périphérique) yang banyak dilakukan oleh kelompok budak, yaitu menyukai sesama jenis. Dengan demikian kelompok borjuis berhasil melakukan pengawasan terhadap kelompok homoseksual yang dikategorikan sebagai “penyakit’’. Pengkategorisasian ini terus melekat sampai pada akhirnya pada permulaan abad ke dua puluh, homoseksualitas dianggap sebagai sebuah “penyakit”.Anggapan ini terus menyebar semakin luas ketika pada era 80-an, seorang bintang Film Amerika, Rock Hudson meninggal dunia karena virus HIV/AIDS, kebetulan saja Hudson adalah seorang gay. Tidak hanya Hudson, seorang penyanyi legendaris dari kelompok Queen, Freddie Mercury juga meninggal dunia akibat virus HIV/AIDS dan lagi-lagi Mercury adalah seorang gay. Maka tidak ayal lagi apabila eksistensi homoseksual, khususnya gay dianggap sebagai orang-orang yang menularkan virus mematikan. Sebagai bentuk pembangkangan kelompok gay terhadap beredarnya isu-isu yang kurang jelas, maka mereka membentuk “sub kultur” baru, yang kita kenal di dunia Barat dengan istilah “gay ghetto”. Istilah “ghetto” sendiri sebenarnya diambil dari sistem pengucilan kelompok Yahudi yang dilakukan pada zaman Nazi. Dengan “gay ghetto”, kelompok gay justru membangun elemen-elemen kekuatanya sendiri dengan membangun “gay bar”, “gay pub”, “sauna gay”, dan sejenisnya. Bahkan mereka juga membangun “sub budaya” sendiri di ranah fashion. Seorang ahli geografi sosial George Chauncey pernah mengatakan bahwa kelompok gay membangun sebuah sistem “sub budaya” yang begitu tinggi dengan menggunakan kode-kode, seperti kode berpakaian, kode berbicara, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan agar supaya mereka dapat melakukan komunikasi dengan sesama gay di jalanan, di pekerjaan, di pesta-pesta.“Komunikasi khusus” dilakukan karena mereka tidak ingin secara potensial dimusuhi oleh orang yang bukan gay. Ketika zaman sudah berubah, sampai sekarang jenis pembangkangan inipun masih ada. Kita dapat melihat, umumnya di kota-kota metropolitan, banyak berjejer “gay bar”, “gay pub” atau “gay sauna” meskipun penyebab virus HIV/AIDS sudah tidak lagi identik penyebarannya oleh orang gay. Kekayaan Budaya Indonesia yang “Beraneka Ragam”: Sebuah Paradoks Homophobia Walaupun pada tahun 1968, beberapa ahli psikologi melalui DSM II (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) telah menghapus homoseksual sebagai sebuah penyakit, namun masih banyak negara yang masih anti terhadap kelompok homoseksual dan menyatakan dirinya sebagai negara yang homophobia. Homophobia membentuk sebuah sistem hierarki seksualitas dan berdampak ke semua bidang. Daniel-Welzer Lang juga mengatakan, ‘’La vision hétérosexuée du monde où la sexualité considérée comme normaleetnaturelle est limitée aux rapports sexuels entre hommes et femmes. Les autres sexualité, homosexualités, bisexualités, sexualité transsexuelles…étant, elles, au mieux définies, voire admises, comme différentes’’ [Visi umum [ideologi] heteroseksual dimana seksualitas [digambarkan] sebagai [sesuatu yang] normal dan alami [adalah] hanya [dikaitkan] dengan laki-laki dan perempuan. Seksualitas yang lain [seperti] homoseksualitas, biseksualitas, seksualitas transeksual, [digambarkan sebagai sesuatu yang] berbeda]. Konteks sosial budaya saat ini, membuat kelompok LGBT dimarjinalkan bahkan dikriminalisasikan. LGBT diasosiasikan dengan perilaku berhubungan seksual dengan cara sodomi dan berhubungan langsung dengan perilaku nenek sihir dan setan, sehingga LGBT selalu dianggap sesuatu yang sangat menyimpang dan anormal. Padahal dahulu kala ketika kepercayaan-kepercayaan animisme masih ada di muka bumi, kelompok LGBT diakui keberadaannya melalui ritual-ritual adat setempat, misalnya kelompok Bissu di Sulawesi Selatan, Warok-Gemblak di Ponorogo, Jawa Timur, kebudayaan Tari Rateb Sadati di Aceh, dan lain sebagainya. Kelompok Bissu misalnya. Mereka adalah laki-laki yang memiliki sifat perempuan yang dianggap suci keberadaannya.Bissu dianggap sebagai perantara antara Tuhan dan manusia di bumi. Ketika masyarakat Bugis misalnya melakukan upacara potong padi atau pada saat pesta pernikahan, Bissu kerapkali harus selalu ada di sana untuk memberkati acara tersebut. Dalam aktivitasnya, Bissu memakai pakaian yang menandakan bahwa mereka adalah lakilaki sekaligus perempuan. Mereka membawa badik untuk memberi tanda bahwa mereka seorang “laki-laki”, sementara itu di atas kepalanya, mereka mengenakan bunga, menandakan bahwa mereka memiliki sifat-sifat seperti perempuan. Menjadi Bissu pun tidak mudah.Mereka harus menjalani ritual-ritual yang sangat panjang dan magis. Seorang Bissu juga harus mampu untuk menghapal bait-bait magis untuk memberkati sebuah acara. Agak berbeda dengan Bissu di Sulawesi Selatan, homoseksualitas juga muncul di dalam kebudayaan Warok Gemblak di Ponorogo, Jawa Timur, dan di dalam tari Rateb Sadati di Aceh.Warok adalah seorang pemimpin tarian Reog dan diyakini memiliki kekuatan magis. Agar kekuatan magisnya tidak hilang, meskipun seorang Warok biasanya memiliki istri, mereka harus “memelihara” anak laki-laki muda yang didandani seperti perempuan. Mereka inilah yang dinamakan Gemblak. Seorang Gemblak adalah tanggung jawab Warok. Gemblak harus “melayani” keinginan Warok. Sebagai wujud rasa terima kasih kepada Gemblak, Warok akan memberikan apa saja yang Gemblak inginkan. Menjadi Gemblak tampaknya bukanlah sesuatu yang tabu dan aneh di Ponorogo.Seorang Gemblak biasanya berasal dari keluarga miskin. Bagi orang tua sang Gemblak, menjadi Gemblak justru dapat meningkatkan kesejahteraan mereka, karena sang Warok akan mensejahterakan hidup sang Gemblak dan keluarganya. Hubungan Warok Gemblak menurut pandangan saya, mungkin saja dapat dipadupadankan dengan “pederasti” di Barat.Aktifitas “pederasti” sangat umum dilakukan pada zaman dahulu kala, misalnya saja Julius Caesar yang memiliki banyak “simpanan” lakilaki muda pada zamannya. Posisi Warok Gemblak dapat dikatakan sebagai hubungan yang romantis. Bagi warga Ponorogo sendiri, Warok Gemblak bukanlah suatu yang harus diperdebatkan. Hubungan Warok Gemblak sudah sangat alami dan terjadi begitu saja. Sama halnya dengan hubungan Warok Gemblak, Aceh pada masa lalu juga pernah mengalami hal yang sama. Pada tahun 1800an, seorang ahli Islam dari Belanda, Snouck Hurgronje menulis dalam bukunya “The Achehnese”, bahwa Ia melihat bagaimana tari Rateb Sadati juga dipenuhi oleh hubungan romantis antara pemimpin tari dengan salah satu penarinya. Tari Rateb Sadati biasanya ditarikan oleh Sembilan anak laki-laki dan dipimpin oleh seorang syekh.Tugas seorang syekh adalah menggiring tarian ini dengan lagu-lagu yang keluar dari mulutnya dengan nada khas senandug Arab. Di antara ke Sembilan anak laki-laki tersebut, biasanya terdapat satu anak laki-laki y ang didandani seperti seorang perempuan dan konon kabarnya anak laki-laki yang didandani itu memiliki hubungan khusus dengan syekh. Biasanya mereka diambil dari kepulauan Nias dari latar belakang keluarga yang miskin. Kebudayaan-kebudayaan tersebut terhempas dan hampir hilang (bahkan sudah ada yang hilang sama sekali) begitu saja pada paruh waktu 1960-an. Pada masa itu, pemerintah Indonesia sedang menumpas komunis dan mereka yang konon kabarnya dianggap “mempratekkan” homoseksualitas dituduh sebagai partisan komunis. Pada akhirnya, mereka diancam untuk segera memeluk agama, dalam hal ini Islam, atau dibunuh. Hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan, maka mereka memilih untuk memiliki agama. Saat ini, meskipun ritual-ritual yang mereka lakukan tetap dijalankan, akan tetapi hanya sebatas pada kepentingan pariwisata, meskipun masih ada juga ritual-ritual yang dijalankan dengan tahaptahap sesungguhnya dengan skala yang kecil. Saya percaya bahwa masih banyak ritual-ritual seperti yang saya jelaskan di atas di Indonesia, akan tetapi mungkin belum tergali sedemikian rupa. Saya sangat berharap, para antropolog di Indonesia mampu menemukan ritual-ritual sejenis di wilayah di Indonesia, sehingga kita sebagai bangsa Indonesia memahami bahwa homoseksualitas di Indonesia sudah ada sebelum agama-agama Samawi mempenetrasi seluruh masyarakat Indonesia. Represi dan Ekspresi Menyikapi duel besar antara mereka yang heteroseksual dan mereka yang homoseksual, Diana Fuss dalam bukunya yang sangat terkenal Inside/out:Lesbian theories, gays theories, memaparkan bahwa ada kelompok-kelompok minoritas seksual tersendiri yaitu gay dan lesbian yang sebenarnya tidak “tampak” tetapi “tampak” di dalam masyarakat. Ini menandakan bahwa ada sebuah sentralitas heteroseksual dan kelompok-kelompok minoritas seksual yang keduanya eksis satu sama. Munculnya dua kelompok besar ini mengisyaratkan bahwa LGBT ada dalam sebuah jaringan dan bentuk. Sebuah represi sosial dan politik yang sangat menekan tentunya akan membungkam kebebasan ekspresi seseorang. Keputusan untuk ‘’Coming out of closet’’(pengakuan akan orientasi seksual) sangat dipengaruhi oleh konsep poststrukturalis Jacques Derrida dan Michel Foucault dan epistemologi-epistemologi kontemporer yang memandang bahwa seseorang bebas menginterpretasikan dirinya masingmasing.Manusia adalah subyek yang memiliki being dan knowledge. Pada awal-awal tahun 1960-an, kebebasan kelompok LGBT, misalnya di Perancis, ditandai dengan adanya komersialisasi industri seks, contohnya dengan pembukaan “gay bar”, “gay pub”, “sauna gay”, “gay cinema”, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu saja, organisasiorganisasi yang khusus mengusung pembebasan kelompok gay juga marak timbul, bahkan pada akhirnya pada tahun 2013 (walaupun sedikit terlambat dari negara-negara Eropa lainnya), pemerintah Perancis sudah melegalkan pernikahan homoseksual. Walaupun demikian, bukan saja tidak sedikit masyarakat Perancis yang masih menentang legalisasi pernikahan ini dengan melihat efek psikologis anak-anak yang diadopsi oleh orang tua gay atau orang tua lesbian. Indonesia mungkin saja ingin menjadi negara di Asia Tenggara yang juga mampu mengakomodir gay, lesbian, biseksual dan transjender dalam menjalankan hidup kesehariannya. Namun, cukup dapat dimengerti bahwa masyarakat Indonesia belum siap untuk dapat menerima LGBT, apalagi dengan “predikat” sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki banyak penduduk Muslim. Efek ini dapat terlihat cukup drastis ketika beberapa minggu yang lalu, pemerintah Amerika Serikat sudah melegalkan pernikahan homoseksual di seluruh negara bagiannya.Banyak sekali masyarakat Indonesia yang sudah salah kaprah menghakimi LGBT Indonesia yang ingin cepat-cepat melegalkan pernikahan homoseksual di Indonesia. Padahal agenda LSM LGBT di Indonesia belum sampai mengarah kesana. Agenda penting yang utama yang diperjuangkan oleh LSM LGBT di Indonesia adalah bagaimana menyadarkan masyarakat Indonesia bahwa LGBT ada di sekitar kita.Agenda untuk mendesak pemerintah Indonesia dalam rangka melegalkan pernikahan homoseksual masih belum ada di dalam agenda mereka.Tulisan ini ingin memberikan sebuah insight bahwa sebagai individu yang bebas, bukan berarti kita bebas untuk menghakimi orang-orang yang tidak sejalan dengan jalan hidup kita; bukan berarti kita bebas melakukan tindakan diskriminasi (verbal atau non-verbal) terhadap gay, lesbian, biseksual dan transjender, yang pada akhirnya dapat saya katakan bahwa LGBT adalah korban dari norma-norma sosial yang ada di dalam masyarakat. *) Wisnu Adihartono adalah kandidat Ph.D. di bidang sosiologi di Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) Marseille, Perancis. Ia mempunyai ketertarikan pada bidang sosiologi gender, gay dan lesbian, sosiologi migrasi, sosiologi keluarga dan sosiologi keseharian (sociology of everyday [email protected]. lifes). Bisa dihubungi melalui email