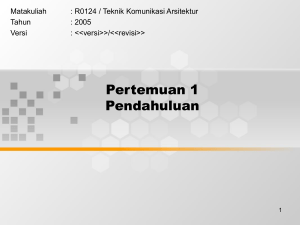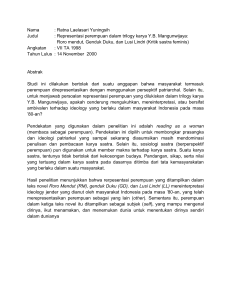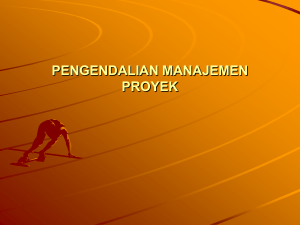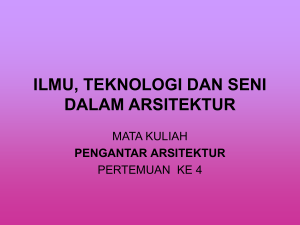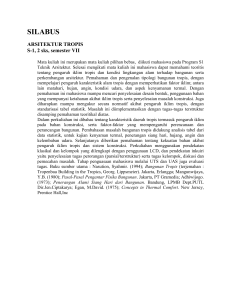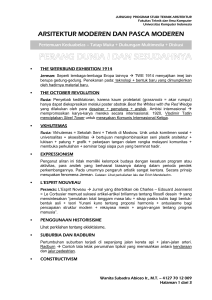Mangunwijaya coins three theories of architecture - Faculty e
advertisement
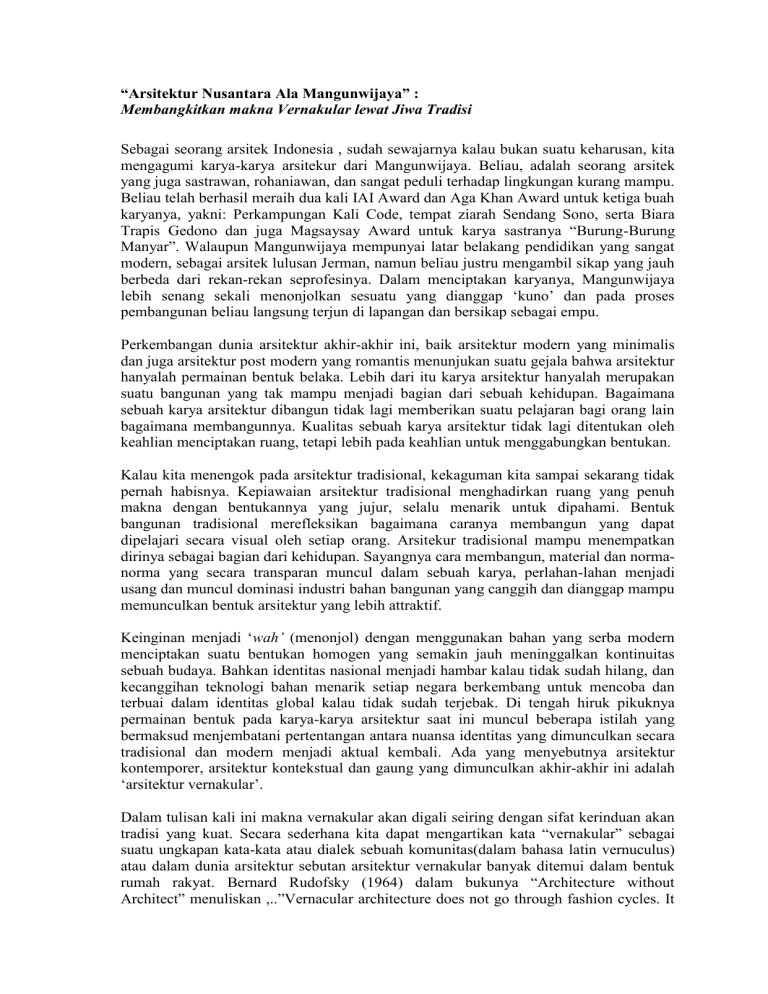
“Arsitektur Nusantara Ala Mangunwijaya” : Membangkitkan makna Vernakular lewat Jiwa Tradisi Sebagai seorang arsitek Indonesia , sudah sewajarnya kalau bukan suatu keharusan, kita mengagumi karya-karya arsitekur dari Mangunwijaya. Beliau, adalah seorang arsitek yang juga sastrawan, rohaniawan, dan sangat peduli terhadap lingkungan kurang mampu. Beliau telah berhasil meraih dua kali IAI Award dan Aga Khan Award untuk ketiga buah karyanya, yakni: Perkampungan Kali Code, tempat ziarah Sendang Sono, serta Biara Trapis Gedono dan juga Magsaysay Award untuk karya sastranya “Burung-Burung Manyar”. Walaupun Mangunwijaya mempunyai latar belakang pendidikan yang sangat modern, sebagai arsitek lulusan Jerman, namun beliau justru mengambil sikap yang jauh berbeda dari rekan-rekan seprofesinya. Dalam menciptakan karyanya, Mangunwijaya lebih senang sekali menonjolkan sesuatu yang dianggap ‘kuno’ dan pada proses pembangunan beliau langsung terjun di lapangan dan bersikap sebagai empu. Perkembangan dunia arsitektur akhir-akhir ini, baik arsitektur modern yang minimalis dan juga arsitektur post modern yang romantis menunjukan suatu gejala bahwa arsitektur hanyalah permainan bentuk belaka. Lebih dari itu karya arsitektur hanyalah merupakan suatu bangunan yang tak mampu menjadi bagian dari sebuah kehidupan. Bagaimana sebuah karya arsitektur dibangun tidak lagi memberikan suatu pelajaran bagi orang lain bagaimana membangunnya. Kualitas sebuah karya arsitektur tidak lagi ditentukan oleh keahlian menciptakan ruang, tetapi lebih pada keahlian untuk menggabungkan bentukan. Kalau kita menengok pada arsitektur tradisional, kekaguman kita sampai sekarang tidak pernah habisnya. Kepiawaian arsitektur tradisional menghadirkan ruang yang penuh makna dengan bentukannya yang jujur, selalu menarik untuk dipahami. Bentuk bangunan tradisional merefleksikan bagaimana caranya membangun yang dapat dipelajari secara visual oleh setiap orang. Arsitekur tradisional mampu menempatkan dirinya sebagai bagian dari kehidupan. Sayangnya cara membangun, material dan normanorma yang secara transparan muncul dalam sebuah karya, perlahan-lahan menjadi usang dan muncul dominasi industri bahan bangunan yang canggih dan dianggap mampu memunculkan bentuk arsitektur yang lebih attraktif. Keinginan menjadi ‘wah’ (menonjol) dengan menggunakan bahan yang serba modern menciptakan suatu bentukan homogen yang semakin jauh meninggalkan kontinuitas sebuah budaya. Bahkan identitas nasional menjadi hambar kalau tidak sudah hilang, dan kecanggihan teknologi bahan menarik setiap negara berkembang untuk mencoba dan terbuai dalam identitas global kalau tidak sudah terjebak. Di tengah hiruk pikuknya permainan bentuk pada karya-karya arsitektur saat ini muncul beberapa istilah yang bermaksud menjembatani pertentangan antara nuansa identitas yang dimunculkan secara tradisional dan modern menjadi aktual kembali. Ada yang menyebutnya arsitektur kontemporer, arsitektur kontekstual dan gaung yang dimunculkan akhir-akhir ini adalah ‘arsitektur vernakular’. Dalam tulisan kali ini makna vernakular akan digali seiring dengan sifat kerinduan akan tradisi yang kuat. Secara sederhana kita dapat mengartikan kata “vernakular” sebagai suatu ungkapan kata-kata atau dialek sebuah komunitas(dalam bahasa latin vernuculus) atau dalam dunia arsitektur sebutan arsitektur vernakular banyak ditemui dalam bentuk rumah rakyat. Bernard Rudofsky (1964) dalam bukunya “Architecture without Architect” menuliskan ,..”Vernacular architecture does not go through fashion cycles. It is nearly immutable, indeed, unimprovable, since it serves its purpose to perfection. Sedangkan Amos Rapoport (1969) dalam bukunya ‘House, Form and Culture’, mengartikan arsitektur vernakular sebagai ‘folk tradition’. Sebenarnya istilah Arsitektur Vernakular sudah muncul pada era 60an, namun saat itu tak banyak arsitek yang menaruh perhatian karena dianggap hanya sebagai arsitektur rakyat dan derajat ke’arsitekturan’nya disepelekan. Namun, ketika seorang kritikus arsitek kelas dunia, Kenneth Frampton (1982), memunculkan istilah “regionalism”, dalam bukunya Modern Architecture and the Critical Present, beliau mengritik gejala universalitas arsitektur modern di seluruh belahan bumi, dan mempertanyakan identitas regional. Dikatakan dalam bukunya ”…Everything will depend on the capacity of rooted culture to recreate its own tradition while appropriating foreign influences at the level of both culture and civilization….. Regionalism is a dialectical expression. It selfconsciously seeks to deconstruct universal Modernism, in terms of values and images which are quintessentially rootes, and at the same time to adulterate these basic references with paradigms drawn from alien sources”. Saat ini issue tentang arsitektur rakyat yang ramah lingkungan mulai banyak diperdebatkan, dan arsitektur vernacular menyimpan jawabannya. Secara popular Arsitektur Vernakular dapat dipahami dengan mudah sebagai sebuah hasil karya arsitektur yang mempunyai sasaran sebuah komunitas/ tempat yang jelas, sehingga mampu memunculkan karakter setempat. Belajar dari rumah-rumah tradisional yang mampu memberikan pelajaran-pelajaran runag, bentuk dan struktur yang menyatu dan jujur. Rumah-rumah rakyat di pedalaman, seperti rumah Honai di Irian Jaya, Rumah Perahu di Kalimantan seringkali kita jumpai sebagai karya anonim yang dibangun oleh masyarakat setempat dengan kemampuan akan konstruksi dan bahan yang dipelajari secara turun temurun dan didapat dari lokasi setempat. Hasil karya ‘rakyat’ ini merefleksikan sebuah masyarakat yang akrab dengan alamnya, kepercayaannya, dan norma-normanya dengan bijaksana. Bentuk, proporsi, dan dekorasinya merupakan simbol-simbol yang berarti. Mereka tidak meletakkan tujuan untuk suatu keindahan tetapi menciptakan ruang dengan prinsip-prinsip kehidupan menghadirkan bentuk struktur yang telah teruji oleh alam. Meminjam istilah Christopher Alexander bahwa arsitektur itu mempunyai bahasa, maka bahasa arsitektur vernakular erat sekali hubungannya dengan aspek-aspek tradisi. Tradisi memberikan suatu jaminan untuk melanjutkan kontinuitas tatanan sebuah arsitektur melalui sistim persepsi ruang yang tercipta, bahan dan jenis konstruksinya. Ruang, bentuk dan konstruksi dipahami sebagai suatu warisan yang akan mengalami perubahan secara perlahan melalui suatu kebiasaan. Perkataan ‘tradisi’, sebenarnya berasal dari bahasa latin “trado – transdo”, yang berarti ‘sampaikanlah kepada yang lain”. Banyak orang mencoba mendefinisikan apa itu tradisi. Namun aspek yang tak dapat dipungkiri bahwa dalam tradisi ada makna untuk melanjutkan ke generasi berikutnya. Oleh sebab itu istilah ‘vernakular’ dan ‘tradisi’ sering kali dipakai bersamaan untuk saling melengkapi. Penghayatan akan tradisi tidak berarti mengharuskan kita hidup kembali seperti di masa lampau. Namun penjiwaan akan sebuah tradisi yang baik akan lebur dalam pikiran kita dan mampu mendorong seorang arsitek untuk menciptakan suatu karya yang mempunyai karakter yang kuat. Dalam tulisan kali ini, saya mengajak para pembaca untuk sejenak kembali melihat apa yang telah diperbuat oleh seorang arsitek Mangunwijaya. Beliau amat mengagumi dan sadar akan kekayaan arsitektur yang diciptakan oleh leluhurnya sendiri. Beliau berupaya untuk berpegang pada kekayaan imajinasinya akan potensi-potensi tradisi setempat. Konsep mengembalikan arsitektur ke prinsip-prinsip dasar yang bersifat lokal mengakar pada dirinya. Latar belakang kehidupan yang beragam sangat berpengaruh pada karyakarya arsitekturnya. Buah karyanya sarat dengan pesan, baik dari segi konsep maupun teknik. Namun, beliau lebih suka disebut sebagai “Arsitektur Nusantara” karena tidak harus mengacu ke gaya-gaya arsitektur tertentu. Mangunwijaya (1985) selalu mengingatkan lewat bukunya “Wastu Citra”, bahwa ternyata bangunan punya citra tersendiri, mewartakan mental, dan jiwa pembuatnya. Dan ternyata pula bila sang arsitek hendak berarsitektur sebaiknya ada kecenderungan lebih mendalami yang berhubungan dengan mental, kejiwaan, serta kebudayaan setempat. Mangunwijaya menyatakan tiga teori arsitektur yang patut untuk dicermati untuk menghasilkan sebuah karya dapat disebut sebagai ‘Arsitektur Nusantara’ Satu, arsitektur adalah simbol dari sebuah kosmos. Kedua, arsitektur adalah cermin dari sebuah gaya hidup. Ketiga arsitektur membutuhkan suatu ekspresi yang mandiri. Karya bangun Mangunwijaya tumbuh dari suatu keakraban dengan alam setempat, dengan penyampaian yang wajar tapi sarat pesan, lihat hasil karya beliau sebuah tempat ziarah untuk umat Katolik di Sendangsono (gambar 1-4). Keinginan Mangunwijaya menghadirkan sebuah substansi untuk mendorong hadirnya arsitekur nusantara terlihat dari penjiwaannya terhadap arsitektur rumah – rumah tradisional dan juga candi di Indonesia. Kesadaran yang total akan menghasilkan karya arsitektur nusantara yang indah pula. Seperti hadirnya bangunan pertapaan biara trappist di Gedono, Salatiga karya Romo Mangunwijaya. Bukankah tatanan kolom, pengangkatan bangunan mencerminkan tatanan rumah tradisional kita? Namun kompleksitas dari tatanan jendela tidak mengacu pada bentuk-bentuk jendela rumah tradisional, tetapi pengulangan tatanan lengkung mengingatkan kita pada bentuk-bentuk lengkung dari pintu candi-candi di jawa tengah. Bukankah perpaduan antara konstruksi kayu dan pemahaman detil konstruksi batu menghadirkan sebuah arsitektur nusantara yang harmoni. (lihat gambar 4-10. Biara trapis di Gedono). Sebagai arsitek, beliau ingin membagikan wawasan bagaimana ber-arsitektur. Di tengah kiprahnya berkarya, beliau masih prihatin terhadap bidang arsitektur yang lebih banyak berpihak pada orang mampu daripada orang tidak mampu, sehingga hal ini mendorong beliau dengan sadar melepaskan atribut keprofesian atau melepas embel-embel IAI di belakang namanya. Kepedulian beliau ini dapat kita lihat dari hasil karyanya sebuah perumahan untuk kaum papa di Kali Code, Jogaykarta. (lihat gambar 10-14) Bagi seorang Mangunwijaya berarsitektur tidak hanya merancang dan membangun, tetapi juga mengkritik dan mendidik. Arsitek seharusnya kembali ke asal mulanya yang menguasai berbagai bidang ilmu dan ketrampilan. Kepiawaian untuk berpikir holistik jarang bersatu atau mengkristal dalam diri seseorang. Begitulah sang Mangunwijaya yang telah mewariskan karya-karyanya untuk kita semua, beliau bukan saja seorang pendidik, tetapi juga seorang pemikir/penulis dan pengkritik yang bijak. Sebagai penutup, saya kutipkan sajak-sajak indah dari nenek moyang kita yang dituliskan kembali oleh seorang arsitek dan sastrawan Mangunwijaya dalam bukunya Wastu Citra (hal 2), “Kang ingaran urip mono mung jumbuhing badan wadaq lan batine, pepindhane wadhah lan isine…. Jeneng wadhah yen tanpa isi, Olah dene arane wadhah, Tanpa Tanya tan ana pigunane. Semono uga isi tanpa wadhah, Yekti barang mokal……. Tumrap urip kang utama tertamtu ambutuhake wadhah la isi, Kang utama karo-karone”. [Yang disebut hidup (sejati) tak lain adalah leburnya tubuh jasmani dengan batinnya, ibarat bejana dan isinya…… Biar bejana tetapi bila tanpa isi, sia-sia disebut bejana, Tidak semestinya dan tidak berguna, Demikian juga isi tanpa bejana, Sungguh hal yang mustahil…. Demi hidup yang baik tentulah dibutuhkan bejana dan isi, Sebaiknyalah kedua-duanya.] Lilianny S Arifin Laboratorium Sejarah & Teori Arsitektur, Jurusan Arsitektur, Universitas Kristen Petra Alamat Rumah : Rungkut Asri Barat 10/31 Surabaya 60293 Telp. Rumah : 031- 8701926 E-mail : [email protected]