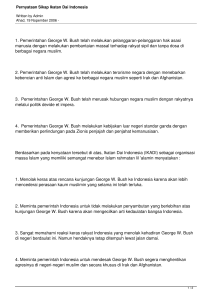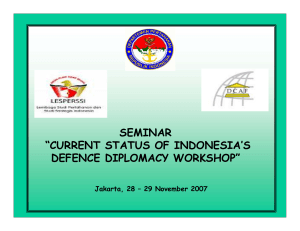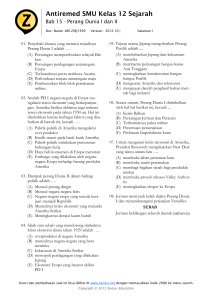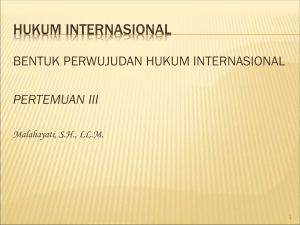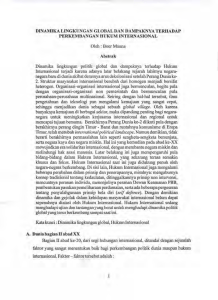Daftar Isi - The Habibie Center
advertisement

Philips J. Vermonte, Reformasi PBB 1 Daftar Isi JURNAL DEMOKRASI & HAM Vol. 3, No. 2, Mei-September 2003 ANALISIS Dewi Fortuna Anwar Tatanan Dunia Baru di bawah Hegemoni Amerika Serikat 7 Riza Sihbudi Pasca Agresi Amerika ke Irak 29 Philips J. Vermonte Reformasi PBB, Masalah Keamanan dan Perdamaian Internasional: Isu dan Pemecahannya 55 Ninok Leksono Dunia dan Isu Pertahanan Pasca Perang Teluk II 74 TELAAH BUKU Rahadi T. Wiratama Bangsa: Antara Bayangan dan Realitas 85 BIODATA PENULIS 91 2 Demokrasi & HAM Vol. 3, No. 2, Mei-September 2003 JURNAL DEMOKRASI & HAM Terbit sejak 20 Mei 2000 ISSN: 1411-4631 Penanggungjawab: Dr. Ahmad Watik Pratiknya Dewan Redaksi: Prof. Dr. Muladi, SH. (Ketua), Dr. Indria Samego, Dr. Dewi Fortuna Anwar, Umar Juoro, MA. MAPE., Ade Armando, MA. Pimpinan Redaksi: Andi Makmur Makka Redaktur Pelaksana: Andrinof A. Chaniago Redaktur: Taftazani, Rudi M. Rizki Sekretaris: Chitra Puspitahati Usaha: Ghazali H. Moesa, Aulia Fitriani, Delianti Naim Sirkulasi: The Habibie Center Gambar Kulit: Alfian Tirtakusuma Layout: Tim IDH-THC Penerbit: The Habibie Center Alamat Penerbit dan Redaksi: Jl. Kemang Selatan No. 98, Jakarta 12560 - Indonesia Telp.: (021) 7817211, Fax: (021) 7817212 Website: http://www.habibiecenter.or.id E-mail: [email protected] EDITORIAL LAHIRNYA ‘the GLOBAL EMPIRE’ Kota Baghdad, masa Mesopotamia lama dari bangsa Sumeria, Babylon, memang sudah berubah. Hanya bekas-bekas tembok Babylon yang menunjang kerajaan dibawah pemerintahan Raja Nebuchadnezzar (abad keenam sebelum masehi) masih ditemukan di Tigris. Jika bukan karena di hancurkan oleh orang-orang Mongol, situs peradaban lama yang kaya itu, sudah disapu oleh banjir, badai padang pasir, selebihnya sudah di buldoser untuk pembukaan jalan baru. Wajah kota Baghdad dan Irak pada umumnya, sekarang penuh dominasi aspirasi pemimpin modern Irak Saddam Husein yang keras dan paling dibenci Amerika Serikat. Baghdad sudah berubah menjadi kota modern. Tetapi Baghdad dan Irak tidak pernah sepi dari sorotan dunia. Terakhir Amerika Serikat dengan mengejutkan telah melancarkan invasi ke Irak dan berhasil menjatuhkan rezim Saddam Husein. Sebuah bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat. Bahkan sampai saat ini, Amerika Serikat, masih meguasai seluruh negara itu dan membentuk pemerintahan baru sebagaimana yang diinginkannya, kendatipun, tindakan Amerika Serikat mengagresi Irak, penuh kontroversi dan bertentangan dengan opini dunia. Seruan dari berbagai penjuru dunia yang meminta dihentikannya agresi, jangan membunuh rakyat Irak hanya untuk minyak serta berbagai bujukan sampai kutukan, tidak membuat Amerika dan sekutunya menghentikan invasi dan agresi itu. Apakah ini karena Amerika menganggap dirinya sebagai “Chosen People” (masyarakat pilihan). Imaji masyarakat pilihan inilah yang mungkin meyakinkan masyarakat Amerika ditakdirkan untuk memimpin dunia. Kerja keras, hemat, persamaan yang jadi prinsip orang-orang Amerika yang puritan, membuat mereka cepat menjadi bangsa besar (bahkan menjadi hyper power), menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai “pemimpin dunia”, Amerika merasa bertanggung jawab atas keamanan dunia. Di belahan dunia mana yang bergolak, Amerika Serikat datang mencampurinya, seperti yang dilukiskan dengan baik 4 Demokrasi & HAM Vol. 3, No. 2, Mei-September 2003 dalam karakter Rambo pada film produksi Amerika. Tetapi tesis ini, mungkin tidak sepenuhnya benar, karena ternyata banyak rakyat Amerika juga jadi penentang cara berpikir seperti ini. Yang dirisaukan, sejak runtuhnya kekuasaan Uni Soviet serta sekutunya yang pernah menciptakan kekuatan “bipolar” berhadapan dengan negara barat yang dipimpin Amerika Serikat, di dunia ini hanya menyisahkan Amerika Serikat sebagai kekuatan tunggal dalam percaturan politik dunia. Dan Amerika Serikat sangat menyadari hal ini, apalagi dalam gengaman pemimpin seperti George Walker Bush. Lihatlah bukti-bukti berikut ini: Perserikatan Bangsa-Bangsa, satusatunya lembaga dunia tertinggi untuk mengatur hubungan antar bangsa tidak dianggap eksistensinya oleh Amerika Serikat. Ketika invasi Amerika Serikat sudah mulai di lancarkan ke Irak, Kofi Annan yang berteriak keras ketika terjadi intervensi Indonesia ke Timor Timur, bahkan penganjur diadilinya militer dan sipil dari pihak Indonesia yang dianggap melakukan pelanggaran HAM berat pasca jajak pendapat di Timor Timur, kini yang menyangkut agresi Amerika Serikat dan pembunuhan rakyat sipil Irak, tidak berbicara nyaring. Anehnya, ia hanya bersuara memperjuangkan bantuan PBB pasca perang, sementara pasukan Irak masih berperang dan rakyat sipil Irak masih jadi sasaran aksi militer oleh pasukan Amerika Serikat. Oposisi dari negara Eropa besar seperti Jerman, Prancis di anggap sepi Amerika Serikat. Opini dunia dan sebagian besar rakyat Amerika yang menentang perang, tidak merubah niat Bush menghancurkan Irak yang diperintah Saddam Husein. Dalam aksi militer, selain dengan Irak, jauh sebelum George Walker Bush jadi presiden, Amerika sudah menunjukkan karakter aslinya sebagai “pengekspor perang” dengan terlibat di Vietnam, Panama, ElSalvador, Haiti, Cuba, dan berikut mungkin Suriah dan Iran. Dalam Perang Teluk Pertama, Jerman dan Jepang yang tidak mendukung secara militer, dipaksa turut membantu perang itu dengan bantuan keuangan. Hegemoni berlanjut, dalam mendikte opini dunia,seperti halnya mengenai hal “terorisme”, misalnya, Amerika Serikat menciptakan opini yang dipaksakan untuk diadopsi oleh seluruh negara lain, seperti apa yang dikehendakinya. Ketika Osama Bin Laden “dituduh” menyerang gedung World Trade Center di New York, seluruh dunia bereaksi dan manggut-manggut apa yang dikotbahkan pemimpin Amerika Serikat mengenai terorisme, termasuk Indonesia. Begitu pula pengertian HAM dan demokrasi, banyak dikaitkan dengan konteks Amerika Serikat dan Editorial 5 negara maju lainnya. Sementara Amerika Serikat terbukti mendukung berbagai rezim, seperti di Gautemala, Nicaragua dan di Amerika Latin yang melakukan pelanggaran HAM terhadap rakyatnya. Israel yang setiap hari membunuh rakyat sipil Palestina, sebagaimana dalam agresi AS ke Irak hanya jadi tontonan waktu santai di seluruh dunia. Dalam media, selama ini Amerika Serikat yang terkenal pendekar kemerdekaan pers, tetapi dalam perang “Badai Gurun” dan invansinya ke Irak, membuktikan kebohongan dan standar ganda Amerika Serikat pada apa yang disebutnya kebebasan pers. Berita wartawan harus di sensor sesuai dengan kebijakan pemerintah, pemilik televisi memecat wartawan yang bersuara lain dengan suara “mesin perang” dari Gedung Putih, contoh Peter Arnett. Pemancar televisi lawan di bom, situs televisi Aljazeera diacak, bahkan Media Watch Amerika Serikat mencaci maki media cetak dan televisi yang beritanya bertentangan dengan berita media utama di AS, contoh penghujatan terhadap Peter Jenning dari ABC. CNN televisi yang menjadi acuan dunia internasional dalam perang Irak, hanya “mengabdi” kepada pemerintahnya dan tanpa malu-malu menyiarkan berita yang tidak benar. Karena itu, kemerdekaan pers di Amerika Serikat selama ini, hanya mitos, mungkin Indonesia lebih maju dalam kebebasan pers. Edward C.Herman dalam buku “Triumph of the Market” melukiskan bagaimana keinginan Amerika Serikat “menswastakan” dunia dan mendominasi ekonomi. Katanya, Amerika Serikat dan tentu negara maju lainnya, selalu ingin mengelola perdagangan melalui tarif, kuota,subsidi, bahkan perampasan dan penguasaan impor, ancaman pembalasan dan pemboikotan. Banyak cara “mengelola” perdagangan dunia ini dilakukan dengan mula-mula menuduh sebuah negara melakukan “perdagangan tidak adil”. Ketika negara yang dituduh gentar, maka mulailah negara itu didikte. Dibalik kekuatannya sebagai negara besar, Amerika Serikat menciptakan “ketergantungan” dalam alur perdagangan yang normal, negara besar memanipulasi cara pedagangan dengan membuat perjanjian bilateral tetapi “menginjak kaki” mitra dagangnya yang kecil. Banyak negara-negara dunia ke tiga, terpaksa patuh dan tunduk atas peraturan sepihak dari Amerika Serikat. Setelah perang dunia ke II, mulai direkayasa pemberian saksi internasional dengan menciptakan lembaga peminjaman dana yang besar, termasuk di dalamnya IMF, Bank Dunia, International Development Bank, semuanya didominasi Amerika 6 Demokrasi & HAM Vol. 3, No. 2, Mei-September 2003 Serikat. Negara-negara kecil, musuh Amerika Serikat biasanya dihukum dengan menghentikan bantuan, lalu diberikan bantuan dari lembaga “internasional” yang terdiri lembaga keuangan swasta. Cara ini ternyata kemudian lebih fatal akibatnya bagi negara kecil dibandingkan dengan pertama. Di sinilah aturan baku Amerika Serikat, IMF dan Bank Dunia akan diberlakukan secara umum. John Gallagher dan Ronald Robinson dalam artikel “The Imperalism of Free Trade”, menulis bahwa cara seperti inilah yang disebut “kebijakan penjajah”. Kebijakan itu misalnya kini disebut: “penciptaan ekonomi terbuka, privatisasi, proteksi hak-hak investor luar negeri, aturan tentang ekspor bahan mentah, dan lain-lain. Semua strategi ekonomi ini, biasanya diterapkan IMF pada negara peminjam dan akrab dengan telinga kita di Indonesia yang sudah terperangkap strategi “The Imperialism of Free Trade” Amerika Serikat. Sebagai “bangsa terpilih”, Amerika Serikat katanya penganjur persamaan hak, tetapi setelah peristiwa World Trade Center, pemerintah Amerika melakukan diskriminasi terhadap warga negara lain. Mahasiswa asing didaftar, dicurigai dan banyak calon mahasiswa yang ditolak masuk ke Amerika Serikat. Jika hal ini terus terjadi, akan muncul suatu hegemoni tunggal yang akan merubah tatanan dunia. Negara Eropa Barat dan Jepang di Asia yang kuat, masih jauh tertinggal dari Amerika Serikat dan kekuatan ekonomi, dana bantuan, kekuatan militer. Runtuhnya Uni Soviet yang sebagian bekas negara anggotanya “sudah dijerat” dana bantuan Amerika Serikat, makin mengukuhkan kekuatan Amerika Serikat sebagai negara besar dan berpengaruh. Negara dunia ketiga yang banyak menerima bantuan lembaga keuangan dunia, makin lemah sebagai negara merdeka dan berdaulat. Negara-negara ini, tidak sanggup lagi mandiri mengelola kebijaksanaan keuangan dan fiskalnya. Diakui atau tidak, Amerika Serikat akan melenggang dalam menciptakan “the Global Empire” atau “kekaisaran global” yang menaklukkan dunia seperti ungkapan Edward C. Hermann. Salah satu contoh yang menguatkan telah dipertontonkan lagi Amerika Serikat dengan menginvasi Irak. (AMM) ANALISIS Tatanan Dunia Baru di bawah Hegemoni Amerika Serikat Dewi Fortuna Anwar Invasi Amerika Serikat (A.S.) ke Irak yang dimulai secara besarbesaran pada tanggal 20 Maret 2003 menyulut kontroversi internasional. Tindakan A.S. ini dipandang banyak pengamat sebagai tonggak sejarah baru dalam hubungan antar bangsa, yang menandai berakhirnya era pasca-Perang Dingin dan dimulainya era Tatanan Dunia Baru di bawah hegemoni Amerika Serikat secara lebih terbuka. Invasi A.S. itu pada awalnya berdalih sebagai upaya untuk melucuti senjata pemusnah massal yang dituduhkan tetap dikembangkan oleh rezim Saddam Hussein, sehingga melanggar sanksi PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa).1 Namun Amerika Serikat menolak membiarkan tim inspeksi senjata PBB melanjutkan tugasnya dengan alasan bahwa Saddam Hussein tidak kooperatif, dan satu-satunya cara yang dapat memaksa Saddam Hussein ialah aksi militer. Walaupun gagal meyakinkan komunitas internasional, termasuk Dewan Keamanan PBB, untuk mendukung aksi militer di Irak mengingat inspeksi senjata yang dilakukan Tim PBB masih berlangsung, A.S. tetap memutuskan untuk menyerang Irak secara unilateral. Dengan didukung segelintir negara 1. Pada akhir tahun 1990 Irak melakukan invasi terhadap Kuwait untuk merebut ladang minyak yang dipersengketakan kedua negara. Agresi Irak tersebut dikecam masyarakat internasional. Dengan mandat dari Dewan Keamanan PBB A.S. memimpin pasukan koalisi pada awal tahun 1991 dalam operasi yang diberi nama Badai Gurun “Desert Storm” untuk memaksa pasukan Irak mundur dari Kuwait. Sejak kekalahannya pemerintahan Presiden Saddam Hussein dijatuhi sanksi PBB, antara lain ia tidak diperkenankan melakukan interaksi ekonomi dengan pihak luar. Irak juga diperintahkan untuk menghancurkan seluruh senjata non-konvensional yang dimilikinya, seperti senjata kimia dan biologis. Perang Irak I berlangsung di bawah pemerintahan Presiden George Bush Sr. 8 Demokrasi & HAM Vol. 3, No. 2, Mei-September 2003 yang termasuk dalam “coalition of the willing”, antara lain Inggris dan Australia, pasukan A.S. menyerbu Irak tanpa mandat PBB. Misi seranganpun bergeser dari perlucutan senjata pemusnah massal menjadi penggulingan terhadap pemerintahan Saddam Hussein serta menggantinya dengan pemerintahan baru di bawah arahan Washington. Serangan militer A.S. ke Irak yang berhasil mencapai misinya menggulingkan rezim Saddam Hussein dalam waktu relatif singkat (20 hari) memiliki implikasi luas. Selain mengubah wajah Irak dan peta politik Timur Tengah sesuai kehendak Washington, aksi unilateral A.S. di Irak telah mengabaikan beberapa prinsip dasar tatanan internasional yang telah terbentuk sejak akhir Perang Dunia II. Menurut pasal 51 Piagam PBB suatu negara hanya diperbolehkan menyerang negara lain sebagai upaya mempertahankan diri melawan agresi militer. Serangan yang dilakukan tanpa provokasi atau alasan yang sah, dianggap sebagai agresi dan tidak sah menurut hukum internasional. Selain untuk mempertahankan diri, aksi militer oleh suatu negara atau kumpulan negara terhadap negara lain hanya dimungkinkan apabila ada mandat dari Dewan Keamanan PBB, misalnya untuk mencegah kejahatan kemanusiaan yang meluas. Piagam PBB sengaja dirancang demikian untuk mencegah pecahnya kembali perang-perang berskala besar seperti terjadi dalam Perang Dunia I (1914-1918) dan Perang Dunia II (19391945). Beranjak dari pengalaman dua perang dunia yang menelan begitu besar korban nyawa dan harta, masyarakat internasional telah berusaha untuk membangun berbagai aturan dan institusi yang disepakati bersama yang mengharamkan penggunaan senjata dalam menyelesaikan konflik. Serangan A.S. terhadap Irak, apapun alasan yang dikemukakan pemerintahan Presiden Bush, secara sengaja mengabaikan Piagam PBB dan mengenyampingkan peran PBB sebagai satu-satunya institusi inter nasional yang memiliki wewenang dan legitimasi untuk mengerahkan kekuatan militer di arena internasional. Serbuan pasukan A.S. ke Irak bukanlah dalam rangka mempertahankan diri, melainkan merupakan tindakan pre-emption atau mendahului, guna mencegah kemungkinan Saddam Hussein memberikan senjata pemusnah massal yang diduga dimilikinya kepada kelompok teroris yang mungkin akan menggunakannya untuk menyerang Amerika Serikat. Namun baik sebelum maupun sesudah perang berlangsung tidak terdapat bukti-bukti yang meyakinkan bahwa Saddam Hussein terlibat dalam serangan teroris ke Amerika Serikat, memiliki kaitan dengan Al-Qaeda ataupun benarbenar memiliki senjata pemusnah massal seperti dituduhkan oleh Dewi Fortuna Anwar, Tatanan Dunia Baru 9 pemerintahan Bush. Dengan melakukan serangan pre-emption terhadap suatu negara berdaulat, berdasarkan asumsi-asumsi ancaman yang masih bersifat spekulatif, A.S. tanpa malu-malu telah menempatkan dirinya di atas hukum internasional yang berlaku, atau menganggap bahwa aturan internasional yang ada tidak mengikat dirinya sebagai satu-satunya negara adidaya. Hal ini merupakan aktualisasi dari doktrin Bush yang menyebabkan A.S. dikecam oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk oleh sebagian sekutunya di Eropa. Makalah singkat ini akan mencoba menguraikan evolusi kebijakan luar negeri dan pertahanan A.S. dari multilateralisme dan deterrence (menangkal) menuju unilateralisme dan pre-emption (mendahului), serta dampaknya terhadap tatanan internasional, terutama terhadap aliansi A.S. dengan Eropa Barat dan peranan PBB. Amerika Serikat Dari Multilateralisme ke Doktrin Bush Predominasi A.S dalam politik internasional, sesungguhnya bukanlah suatu hal baru. Abad ke dua puluh telah dinyatakan sebagai abad Amerika. Ketika Perang Dunia II berakhir secara relatif kekuatan A.S. dibandingkan dengan negara-negara lainnya semasa itu lebih besar daripada sekarang ini. A.S. merupakan satu-satunya negara yang berhasil keluar dari Perang Dunia II dengan kekuatan utuh, dengan kemampuan ekonomi, militer dan teknologi yang jauh melebihi negara manapun di dunia waktu itu. Sebagian besar negara-negara Eropa hancur akibat Perang Dunia. Eropa Barat yang luluh lantak dibangun kembali oleh A.S. melalui program Marshall Plan. Jerman dan Jepang yang kalah perang diduduki oleh pasukan A.S., sementara sistem politik dan ekonomi kedua negara tersebut juga dibangun kembali oleh Washington. Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina (RRC) yang kemudian tampil sebagai saingan ideologis dan militer A.S. dalam Perang Dingin juga menderita kerugian yang tidak sedikit dari serbuan Jerman (Uni Soviet) dan pendudukan Jepang (Cina). Dibandingkan dengan situasi sekarang ini, di mana di samping A.S. juga ada kekuatan ekonomi lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu Uni Eropa dan Jepang, serta munculnya RRC sebagai kekuatan yang semakin diperhitungkan, posisi A.S. pada era awal pasca- Perang Dunia II jelas lebih dominan.2 2. Peter Howard, “Endgames: Washington, UN, and Europe”. Foreign Policy in Focus, Interhemispheric Resource Center (IRC). 28 Februari, 2003 10 Demokrasi & HAM Vol. 3, No. 2, Mei-September 2003 Namun dengan posisi yang sangat dominan tersebut, A.S. tidak mengembangkan kebijakan unilateral seperti sekarang ini. Sebaliknya, A.S. justru menjadi penggerak utama lahirnya berbagai aturan dan institusi internasional serta kerjasama multilateral, baik pada tingkat regional maupun global. Dalam kurun waktu yang singkat setelah Perang Dunia II berakhir pada tahun 1945 organisasi Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) didirikan, disusul oleh badan-badan internasional lainnya seperti IMF (International Monetary Fund) dan Bank Dunia. Dalam badan-badan tersebut A.S. merupakan aktor utama dan penyandang dana utama. Masyarakat internasional juga mengeluarkan serangkaian perjanjian internasional yang mengatur hubungan antar negara, seperti Piagam PBB, The Genocide Convention, Konvensi Jenewa tahun 1949, Universal Declaration of Human Rights serta GATT (General Agreement on Tariff and Trade). Seluruh peraturan, perjanjian dan institusi-institusi internasional tersebut ditujukan untuk memelihara perdamaian dunia serta untuk meningkatkan kemakmuran secara lebih merata melalui sistem perekonomian yang lebih terbuka. Interdependensi ekonomi juga akan berdampak positif dalam memelihara hubungan damai antar bangsa. Idealisme pasca Perang Dunia II adalah terwujudnya suatu tatanan dunia baru yang lebih beradab, di mana peperangan antar- negara untuk memperebutkan pengaruh dan sumber daya ekonomi tidak lagi mendominasi hubungan internasional. Selanjutnya persaingan dan konflik akan diselesaikan berdasarkan hukum-hukum internasional melalui lembaga-lembaga internasional yang sengaja diciptakan untuk itu. Dengan kata lain hubungan internasional hendak dikelola melalui proses multilateral yang mengharuskan adanya konsultasi dan kesepakatan antara para anggotanya. Idealisme tentang Tatanan Dunia baru yang damai yang sepenuhnya diatur oleh hukum internasional, di mana PBB menempati posisi sentral, memang tidak berlangsung lama. Munculnya Perang Dingin antara Blok Barat yang kapitalis di bawah pimpinan A.S. dan Blok Timur yang komunis di bawah pimpinan Uni Soviet sejak akhir tahun 1940-an meningkatkan kembali peranan kekuatan militer sebagai unsur utama dalam hubungan internasional. Masing-masing blok mengembangkan kemampuan militer, termasuk senjata nuklir, untuk menangkal lawannya. Dengan demikian politik internasional selama Perang Dingin terutama dibentuk oleh sistem perimbangan kekuatan (balance of power) yang cenderung mengecilkan peranan PBB. Dewi Fortuna Anwar, Tatanan Dunia Baru 11 Sesungguhnya komposisi Dewan Keamanan PBB yang terdiri dari lima anggota tetap yang masing-masing memiliki hak veto merupakan cerminan dari sistem perimbangan kekuatan. Kelima anggota tetap Dewan Keamanan PBB adalah negara-negara yang berada pada pihak yang menang dalam Perang Dunia II, yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, Britania, Perancis dan Cina.3 Peran PBB tidak jarang disandera oleh kebijakan negara-negara adidaya, terutama dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan langsung Amerika Serikat atau Uni Soviet. PBB sering tidak dapat mengambil sikap tegas terhadap suatu permasalahan karena di veto oleh salah satu anggota tetap Dewan Keamanan. Namun walaupun di satu pihak peranan PBB relatif lemah, Perang Dingin justru memaksa pihak-pihak yang berkonflik untuk mendukung hukum internasional serta mengembangkan sistem multilateral karena beberapa hal. Pertama, baik A.S. maupun Uni Soviet menyadari bahwa konflik terbuka di antara mereka akan mengakibatkan kehancuran total, mengingat kemampuan senjata nuklir yang dimiliki masing-masing dapat menghancurkan dunia berkali-kali. Dengan demikian kedua negara adidaya dipaksa untuk menahan diri dan mematuhi prinsip-prinsip dasar hukum internasional yang melarang suatu negara melakukan agresi terhadap negara lain. Meskipun mereka bersaing dan saling menjegal, kedua negara adidaya menyadari bahwa mereka juga harus tetap bekerja sama untuk mencegah terjadinya perang terbuka di antara mereka. Kedua, baik A.S. maupun Uni Soviet bersaing merebut pengaruh global sehingga masing-masing pihak berusaha tampil sebagai pihak yang benar. Pelanggaran terhadap hukum internasional oleh salah satu pihak akan mer ugikan citra negara yang bersangkutan dan menguntungkan pihak lawan. Perseteruan antara A.S. dan Uni Soviet bukanlah sekedar perseturuan antara dua kekuatan militer tradisional. Perang dingin merupakan konflik antara dua sistem secara total, meliputi ideologi, sistem politik, sosial dan ekonomi yang oleh masing-masing pihak hendak dikembangkan secara universal. Ketiga, persaingan global yang berkembang selama Perang Dingin memaksa kedua adidaya untuk memperkuat dirinya dengan membentuk 3. Sampai tahun 1975 kursi Cina di PBB diisi oleh Taiwan. Namun setelah normalisasi hubungan A.S. dengan RRC, kursi Cina di PBB diisi oleh RRC, sementara Taiwan tidak lagi diakui sebagai negara yang berdaulat sehingga tidak memiliki perwakilan di PBB. 12 Demokrasi & HAM Vol. 3, No. 2, Mei-September 2003 aliansi-aliansi pertahananan, serta membujuk negara-negara netral untuk tidak berpihak pada blok lawan. Dengan demikian selama Perang Dingin berlangsung baik A.S. maupun Uni Soviet tidak leluasa melakukan tindakan unilateral, terutama apabila tindakan tersebut dapat merugikan kepentingan langsung salah satu negara adidaya. Kendati jelas merupakan kekuatan hegemon, selama ini peranan A.S. tidak terlalu dipermasalahkan oleh negara-negara yang berada di bawah naungannya karena Washington lebih banyak menjalankan “soft power”, daripada “hard power”, yaitu menerapkan hegemoni melalui upaya-upaya persuasi dan pengaruh daripada melalui tekanan dan ancaman semata. Sebelum doktrin Bush lahir pada tahun 2002 predominasi A.S. dalam percaturan internasional memiliki tiga tonggak utama, yaitu kekuatan ekonomi, kekuatan militer dan peranan A.S. dalam institusi-institusi multilateral.4 A.S. memberikan bantuan ekonomi langsung pada sekutusekutunya atau negara-negara yang dianggapnya bersahabat, baik melalui bantuan uang seperti sewaktu Marshall Plan di Eropa Barat, ataupun dengan membuka pasarnya terhadap ekspor dari negara-negara tersebut. Dengan kekuatan militernya yang sangat besar A.S. juga bertindak sebagai pelindung keamanan bagi sekutu-sekutunya, misalnya dengan mendirikan aliansi militer multilateral NATO (North Atlantic Treaty Organisation) di Eropa Barat serta aliansi pertahanan bilateral, misalnya dengan Jepang dan Korea Selatan, di mana Washington merupakan “sumbu” (hub) sementara para sekutunya merupakan jari-jari (spokes) dalam sistem pertahanan tersebut. Pengaruh A.S. juga dirasakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui berbagai institusi internasional di mana A.S. merupakan pemegang saham terbesar. Seperti telah disinggung sebelumnya sampai tahun-tahun terakhir ini, A.S. masih merupakan pendukung utama sistem multilateral, misalnya dalam melahirkan WTO (World Trade Organisation) dan Kyoto Protocol tentang lingkungan hidup. Selama Perang Dingin, negara-negara komunis tentu saja melihat A.S. sebagai ancaman dan musuh yang harus dilawan. Namun bagi sebagian besar negara-negara lainnya A.S. cenderung dilihat sebagai “benign superpower”, yaitu adidaya yang bersahabat dan tidak perlu ditakuti. Di samping itu, walaupun banyak negara tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat mereka tetap mengagumi 4. Pierre Hassner, “Definitions, Doctrines, and Divergences”. The National Interest, Number 69, Fall 2002, hal.33. Dewi Fortuna Anwar, Tatanan Dunia Baru 13 keunggulan-keunggulan yang dimiliki A.S., terutama kemajuan perekonomiannya, keunggulan teknologinya, sistem politiknya maupun dinamika kehidupan bermasyarakatnya. Melalui proses globalisasi yang juga dimotori oleh Amerika Serikat, terutama oleh perusahaanperusahaan multinasionalnya, sebagian besar masyarakat dunia telah menjadikan A.S. sebagai rujukan utama nilai-nilai yang mereka anut dan kembangkan dalam proses modernisasi negara masing-masing. Namun sejak keputusan A.S. untuk menyerang Irak tanpa persetujuan Dewan Keamanan PBB, citra A.S. sebagai “benign superpower” sirna. Demontrasi anti- perang secara besar-besaran di berbagai belahan dunia, termasuk di negara-negara sekutu A.S. sendiri, menunjukkan bahwa kini Washington dipandang sebagai agresor. Walaupun A.S. berdalih bahwa serangannya ke Irak adalah untuk membebaskan rakyat Irak dari tirani rezim Saddam Hussein, namun sebagian besar masyarakat internasional melihat tindakan tersebut sebagai perang yang tidak sah, dan kehadiran pasukan A.S. di Irak sebagai pendudukan atas negara yang berdaulat. A.S. dewasa ini telah menampakkan dirinya sebagai kekuatan hegemon yang tidak segan bertindak sendiri tanpa dukungan negaranegara lain, dan tanpa perlu mengindahkan aturan-aturan internasional, walaupun tindakan unilateralnya dilakukan atas nama penegakan hukum internasional. Adalah suatu ironi Presiden Bush memerintahkan penyerangan terhadap Irak dengan melanggar Piagam PBB, untuk menghukum Saddam Hussein yang dituduhnya telah melanggar resolusi PBB tentang pemusnahan senjata massal. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa A.S. memutuskan untuk meninggalkan proses multilateral yang dulu dibangunnya, dan apakah sistem unipolar yang hendak diterapkan Washington di bawah pemerintahan Presiden George W. Bush akan dapat dipertahankan oleh A.S. secara berkelanjutan? Atau apakah kebijakan A.S. tersebut justru akan memunculkan perlawanan dan upaya-upaya untuk membangun kembali kekuatan pengimbang serta penguatan peranan PBB? Ada beberapa faktor yang mendorong munculnya sikap arogansi dan kecenderungan unilateral A.S. Pertama adalah rubuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin sehingga A.S. merupakan satu-satunya negara adidaya yang tersisa. Dengan sendirinya tidak ada lagi kekuatan pengimbang yang setara yang mampu bertindak sebagai penghalang apabila A.S. betul-betul berkeinginan untuk mengambil tindakan sesuai kepentingannya sendiri, terlepas dari sikap negara-negara lain. Demokrasi & HAM Vol. 3, No. 2, Mei-September 2003 14 Kedua, kekuatan ekonomi A.S. yang sedemikian dominan, melebihi Uni Eropa dan Jepang, dua kekuatan ekonomi terbesar lainnya. Asumsi bahwa globalisasi ekonomi semakin meningkatkan saling ketergantungan antara negara-negara di dunia ternyata tidak sepenuhnya benar, karena yang terjadi adalah hubungan asimetris, di mana negara berkembang jauh lebih tergantung pada negara-negara maju daripada sebaliknya. Ketergantungan A.S. pada perdagangan internasional relatif rendah mengingat 90% dari produksinya adalah untuk konsumsi dalam negeri, sementara pasar A.S. merupakan tujuan ekspor utama bagi negaranegara lain.5 Ketiga, kenyataan bahwa kemampuan militer A.S. merupakan yang terbesar di dunia dan cenderung meningkat, walaupun Perang Dingin telah berakhir. Selama Perang Dingin politik internasional mengalami militerisasi, di mana kemampuan militer menjadi penentu utama hubungan antara A.S. dan Uni Soviet. Setelah Perang Dingin berakhir sebagian negara yang terlibat langsung dalam konflik, seperti Rusia dan negara-negara Eropa Barat mengurangi anggaran militer mereka, berbeda dengan A.S. yang tetap memiliki anggaran militer yang tinggi seperti sewaktu Perang Dingin masih berlangsung. Anggaran belanja militer A.S. melebihi total anggaran militer tujuh negara dengan belanja militer terbesar lainnya. Kenyataan ini membuat jurang kemampuan militer antara A.S. dan negara-negara lainnya, termasuk sekutusekutunya dalam NATO, semakin lebar.6 Ketiga faktor di atas menunjukkan bahwa sebagai negara Amerika Serikat dewasa ini berada dalam kelas tersendiri, dengan kemampuan yang tidak tertandingi oleh negara manapun ataupun oleh gabungan beberapa negara sekalipun. Tidaklah mengherankan apabila tidak ada satu negarapun yang secara terbuka berani menantang keperkasaan A.S. (kecuali Irak di bawah Saddam Hussein), walaupun banyak negara yang kritis terhadap kebijakan Washington. Posisi yang ditempati A.S. sekarang melebihi kekuasaan Britania Raya di puncak kejayaan empirumnya pada abad ke-19, dan hampir serupa dengan kekuasaan Kekaisaran Romawi di masa jayanya. 5. Kenneth N. Waltz, “Globalization and American Power”. The National Interest, Number 59, Spring 2000, hal. 49-50. 6. Ibid. hal. 54. Dewi Fortuna Anwar, Tatanan Dunia Baru 15 Namun memiliki kemampuan yang tidak tertandingi tidak serta merta menyebabkan A.S. mesti bertindak unilateral. Di samping kemampuan dan kesempatan, faktor penentu lainnya adalah kemauan. Seperti telah disinggung sebelumnya, pada tahun-tahun pertama setelah Perang Dingin berakhir Washington tetap menunjukkan komitmennya pada proses multilateral. Dalam Perang Teluk tahun 1991 Presiden George Bush (ayah dari Presiden George Walker Bush) berupaya mendapatkan mandat dari Dewan Keamanan PBB serta menggalang pasukan koalisi yang betul-betul berasal dari banyak negara untuk memaksa Saddam Hussein keluar dari Kuwait, walaupun secara militer pasukan A.S. mampu melakukannya sendiri. Presiden Bill Clinton selama delapan tahun berkuasa (1992-2000) juga menunjukkan dukungan yang kuat terhadap proses multilateral, termasuk mendorong dibentuknya organisasi-organisasi regional baru. Hal ini terlihat misalnya dari dukungan A.S terhadap APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) yang melakukan pertemuan tingkat tinggi buat pertama kalinya pada tahun 1992 di Seattle, A.S. atas undangan Clinton, dan pembentukan ASEAN Regional Forum (ARF) pada tahun 1993. Clinton juga memainkan peranan besar dalam pembentukan WTO sebagai badan pengganti GATT dan mencegah Uni Eropa menjadi terlalu proteksionis dalam kebijakan ekonominya. Pemerintah A.S., khususnya wakil Presiden Al Gore, juga menjadi motor utama lahirnya Kyoto Protocol untuk melindungi lingkungan hidup, antara lain melalui pengurangan emisi. Memang di bawah pemerintahan Presiden Clinton dalam beberapa kesempatan A.S. juga melakukan tindakan unilateral, misalnya melakukan beberapa kali serangan udara terhadap Irak, Afghanistan dan Kenya, yang terakhir bahkan sebagai balasan atas pemboman kedutaan besar A.S. oleh sekelompok teroris, walaupun dalam skala yang relatif kecil. A.S. bersama NATO juga melakukan serangan udara terhadap Serbia di Kosovo pada tahun 1999 untuk menghentikan pembantaian yang dilakukan oleh tentara Serbia terhadap penduduk Muslim di sana. Serangan NATO tersebut dilakukan tanpa mandat Dewan Keamanan PBB, karena ditentang Rusia dan RRC. Hanya saja tindakan-tindakan unilateral terdahulu berskala kecil, sebagai balasan atas berbagai serangan teroris terhadap kepentingan A.S. di luar negeri. Walaupun memicu kontroversi serangan unilateral NATO ke Kosovo tidak menimbulkan kecaman internasional karena tindakan tersebut dilihat sebagai “humanitarian intervention” atau intervensi kemanusiaan 16 Demokrasi & HAM Vol. 3, No. 2, Mei-September 2003 guna mencegah kejahatan kemanusiaan yang sedang berlangsung. Namun secara keseluruhan selama pemerintahan Clinton, A.S. tampaknya tetap mendukung sistem multilateral dan mengutamakan upaya-upaya damai untuk mengatasi berbagai konflik internasional, misalnya dengan mendorong terjadinya dialog di Semenanjung Korea dan di Timur Tengah. Dukungan Presiden Clinton pada proses multilateral dan kerjasama internasional merupakan refleksi ideologi liberal yang dianut presiden dari Partai Demokrat tersebut. Dalam pandangan kelompok liberal, yang juga sering disebut “merpati” karena lebih mengutamakan penggunaan diplomasi daripada militer dalam menyelesaikan konflik, A.S. tetap harus bekerjasama dengan negara-negara lain untuk memajukan kepentingan global secara keseluruhan. Kepemimpinan A.S. diraih melalui penggunaan “soft power” dengan tetap memperhatikan aspirasi negaranegara lain, terutama negara-negara sahabat. Dalam perspektif liberal hubungan internasional tidak lagi semata-mata diwarnai oleh kompetisi antar-negara di mana kemampuan militer merupakan komponen utama, tetapi juga bercirikan ker jasama dalam satu jaringan saling ketergantungan. Walaupun A.S. merupakan satu-satunya negara adidaya ia tidak dapat seenaknya memaksakan kehendaknya pada negara lain apabila ia ingin tetap diterima sebagai anggota jaringan. Perspektif liberal ini bertolak belakang dengan pandangan kelompok “realist” yang tetap menilai bahwa politik internasional didominasi oleh persaingan militer antar-negara untuk menentukan negara mana yang paling dominan. Politik luar negeri A.S. mengalami perubahan fundamental ketika Presiden Clinton digantikan oleh Presiden George W. Bush. Berbeda dengan Presiden Bush Senior yang memiliki pengalaman luas dalam hubungan internasional dan cenderung multilateralis, karena pernah menjabat sebagai Direktur CIA dan Duta Besar di RRC, Presiden Bush Junior tidak memiliki pengalaman diplomasi sama sekali. Walaupun Jenderal Colin Powell yang dianggap sebagai seorang tokoh moderat dan pendukung multilateralisme ditunjuk menjadi Menteri Luar Negeri, Bush sendiri cenderung berpendirian unilateralist. Di samping itu anggota Kabinet Bush dalam bidang luar negeri dan pertahanan didominasi oleh tokoh-tokoh konservatif yang berpandangan unilateralist. Mereka ini antara lain adalah Wakil Presiden Dick Cheney, Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld, Richard Perle (Kepala Dewan Kebijakan Pertahanan), Paul Wolfowitz (Wakil Menteri Pertahanan), Dewi Fortuna Anwar, Tatanan Dunia Baru 17 John Bolton (Asisten Menlu bidang Kontrol Senjata) dan Lewis Libby (Kepala Staf kantor Wakil Presiden).7 Dalam pandangan kelompok konservatif yang memiliki perspektif “realist” garis keras ini prioritas luar negeri A.S. adalah melindungi kepentingan nasional A.S. sendiri, terutama keamanan nasional, tanpa perlu mempertimbangkan komitmen-komitmen internasional yang selama ini mengikat Washington. Sebagai negara adidaya, A.S. harus berani bertindak sendiri untuk melindungi kepentingan nasionalnya serta tidak perlu ragu menggunakan kekuatan militer untuk mencapai tujuan, karena militer dianggap sebagai instrumen yang sah dalam politik internasional. Bagi kalangan konservatif garis keras ini bagaimana pandangan negara-negara lain atas tindakan-tindakan unilateral A.S. sama sekali tidak menjadi pertimbangan. Majalah Time menulis bahwa Menteri Luar Negeri Colin Powell yang begitu populer karena perannya dalam Perang Teluk sama sekali tidak berdaya dalam Kabinet Bush. Kendati Powell sendiri dinilai sebagai seorang penganut aliran konser vatif: “Powell is a multilaterallist; other Bush advisers are unilateralists. He’s internationalist; they are America first”. Pandangan Powell dikatakan sebagai “compassinonate conservatism”, atau konservatisme yang memiliki kepedulian pada pihak lain, sementara kelompok garis keras sama sekali tidak peduli pada hal-hal di luar kepentingan A.S.8 Jauh sebelum serangan teroris tanggal 11 September 2001 yang menghancurkan World Trade Center di New York dan merusak sebagian bangunan Pentagon, kantor Departemen Pertahanan di Washington, kalangan konservatif telah berupaya memajukan visi mereka tentang peranan A.S. dalam membentuk tatanan dunia baru pasca-Perang Dingin. Salah satu visi tersebut ialah untuk menjaga ketertiban dunia dengan mempertahankan hegemoni A.S., terutama keunggulan militernya, serta mencegah negara lain untuk membangun kemampuan yang dapat menyaingi hegemoni A.S. tersebut, terutama di wilayahwilayah strategis seperti Eropa Barat, Asia Timur, wilayah bekas Uni Soviet dan Asia Barat Daya.9 Visi ini memandang Tatanan Dunia Baru 7. Time, September 10, 2001. hal.32-33. 8. Ibid. hal 31. 9. Paul Wolfowitz, “Remembering the Future”. The National Interest. Number 59. Spring 2000, hal.36. Demokrasi & HAM Vol. 3, No. 2, Mei-September 2003 18 sebagai Pax Americana, di mana kepemimpinan A.S. dalam menentukan bentuk serta aturan politik internasional tidak menghadapi tantangan dari para pesaing. Hal ini terlihat dari draft memo yang ditulis Wolfowitz ketika menjabat sebagai asisten di Departemen Pertahanan pada tahun 1992 yang bocor ke pers sehingga memicu kontroversi. Makalah tersebut kemudian terbit dengan judul Defence Planning Guidance for 1992-1994. Di samping itu diusulkan bahwa A.S. menggunakan doktrin pre-emptive strike, atau mendahului menyerang potensi musuh secara unilateral apabila pasukan gabungan tidak dapat dibentuk.10 Namun selama pemerintahan Presiden Bill Clinton, doktrin pre-emptive strike ini tidak dipakai. Bagi kelompok konservatif yang menganut paham realist, hegemoni A.S. dalam percaturan politik global merupakan konsekuensi logis dari kekalahan Uni Soviet dan kemenangan A.S. dalam Perang Dingin. Mereka tentu tidak ingin melihat kemunculan perimbangan kekuatan baru menggantikan Uni Soviet yang kembali dapat memicu kompetisi dan ketidakstabilan global. Dalam visi Pax Americana A.S. bertindak sebagai polisi dunia, dengan mandat dan acuan tugas yang dapat ditentukannya sendiri. Seperti dikatakan Wolfowitz, visi Pax Americana ini sesungguhnya juga dianut oleh kelompok liberal, walaupun dalam mencapai tujuan kalangan liberal lebih mendukung pendekatan multilateralist. Yang menentang hanyalah kelompok isolasinist yang ultra-kanan seperti Pat Buchanan.11 Perbedaan antara kelompok konservatif tradisional yang menganut paham realist dengan kalangan konservatif baru (Neo-Conservative) seperti Wolfowitz adalah yang pertama tidak terlalu peduli tentang isuisu demokrasi dan hak asasi manusia, sementara yang kedua melihat bahwa Pax Americana juga ditujukan untuk memajukan demokrasi dan HAM secara global. Dalam hal ini kelompok konservatif baru memiliki tujuan yang serupa dengan kelompok liberal, hanya saja dalam cara pencapaian tujuan mereka berbeda, yaitu yang pertama tidak segan menggunakan kekuatan militer secara unilateral apabila dinilai perlu, sementara kelompok kedua cenderung memilih menggunakan sanksi 10. Lihat Bara hasibuan, “Kaum Neo-Cons di Balik Perang Irak”. Kompas, 14 April 2003. 11. Wolfowitz ibid. Dewi Fortuna Anwar, Tatanan Dunia Baru 19 non-militer, baik melalui PBB maupun secara bilateral untuk menghukum rezim yang dianggap salah.12 Sebelum perang Irak yang membuat posisi A.S. terisolasi, kebijakan unilateral A.S. di bawah pemerintahan Presiden Bush juga telah mengundang banyak kritik, termasuk dari negara-negara sekutu A.S. sendiri. Atas desakan kalangan industri besar pemerintahan Bush menolak meratifikasi Kyoto Protocol untuk mengurangi pengeluaran emisi. Mengingat A.S. adalah negara yang memproduksi emisi terbesar di dunia, tindakan sepihak A.S. tersebut jelas semakin mempersulit per juangan internasional untuk melindungi lingkungan hidup. Kebijakan Washington tersebut dikecam luas, terutama oleh negaranegara Eropa Barat. Hubungan A.S. dengan Rusia dan RRC juga menjadi tegang ketika pemerintahan Bush menyatakan ingin kembali mengembangkan pertahanan misile nasional (national missile defence) untuk melindungi wilayah A.S. dari serangan intercontinental ballistic missiles. Ini berarti secara sepihak akan keluar dari Anti-ballistic Missile Treaty yang ditandatangani pada tahun 1972. Kebijakan ini juga membuat sekutu-sekutu A.S. di Eropa Barat khawatir karena A.S. hanya terfokus pada perlindungan tanah airnya sendiri tanpa mempedulikan keamanan sekutu-sekutunya. Tindakan unilateral A.S. lain yang juga mengundang banyak kecaman adalah penolakan A.S. atas dibentuknya Mahkamah Kriminal Internasional (International Criminal Court), karena A.S. khawatir tentaranya yang tersebar diberbagai pelosok dunia akan banyak yang diseret ke pengadilan tersebut. Mahkamah ini merupakan bagian dari upaya masyarakat internasional untuk menegakkan hak asasi manusia (HAM), agar orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran HAM berat dapat diseret ke pengadilan internasional apabila negaranya sendiri gagal mengadilinya. Ketiga kasus di atas secara jelas menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Bush Jr. menjadikan kepentingan nasional A.S. secara sempit sebagai acuan utama dalam mengelola hubungannya dengan dunia luar, tanpa memperdulikan komitmen-komitmen multilateral atau nilai-nilai 12. Namun menarik untuk disimak bahwa dalam artikelnya yang dikutip di atas Wolfowitz juga menjelaskan bahwa demokrasi tidak bisa dipaksakan dari luar. Demokrasi hanya mungkin tercipta apabila ada dukungan dari dalam negeri yang bersangkutan. Wolfowitz juga mengatakan bahwa leverage yang dimiliki A.S. untuk memaksakan perubahan terbatas. 20 Demokrasi & HAM Vol. 3, No. 2, Mei-September 2003 universal yang dulu justru gigih diperjuangkan Amerika Serikat. Namun sebelum peristiwa 11 September 2001 unilateralisme A.S. lebih berorientasi ke dalam, yaitu untuk melindungi kepentingan A.S. secara langsung, tanpa mengubah tatanan internasional yang berlaku. Situasi berubah setelah serangan teroris yang menghancurkan WTC mempermalukan negara adidaya tersebut, dan membuatnya untuk pertama kali merasa sangat terancam dan tidak berdaya. Dengan menggunakan kekuatan militernya yang tidak tertandingi kebijakan unilateralisme A.S. akhirnya diarahkan ke luar, tidak saja untuk menghancurkan ancaman atau potensi ancaman, tetapi juga untuk mengubah lingkungan strategis sesuai perspektif dan kepentingan Washington. Pada awalnya serangan teroris ke A.S. memaksa Washington untuk mengurangi sikap unilateralismenya. A.S. menyadari bahwa terorisme merupakan ancaman transnasional sehingga untuk menghadapinya diperlukan kerjasama internasional. Masyarakat internasionalpun menunjukkan simpati pada kerugian yang diderita A.S. A.S. berhasil menggalang dukungan dan partisipasi internasional untuk menyatakan “perang” terhadap terorisme. Namun kebijakan multilateral melawan terorisme, yang mengedepankan kerjasama internasional dalam bidang intelijen, memberantas pencucian uang dan kegiatan-kegiatan non-militer lainnya, kembali dikalahkan oleh kecenderungan unilalteralisme dan militerisme para pembuat kebijakan di Washington. Serangan teroris ke A.S. membuka peluang bagi kelompok konservatif dalam pemerintahan Bush untuk merealisasikan doktrin preemptive strike yang sudah lama mereka kemukakan, untuk memusnahkan ancaman maupun potensi ancaman dari manapun sumbernya. Para teroris yang menabrakkan pesawat ke gedung WTC dan Pentagon disinyalir merupakan anggota dari Al-Qaeda, organisasi teroris Islam ekstrim di bawah pimpinan Osama bin Laden yang bermukim di Afghanistan. Walaupun para teroris tidak bertindak atas nama suatu negara, dan terorisme merupakan ancaman non-tradisional yang dilakukan oleh aktor-aktor non-negara, Washington membalas serangan tersebut seolah-olah sedang menghadapi agresi militer konvensional. Yakin atas keterlibatan Osama bin Laden dan Al-Qaeda meskipun bukti-bukti belum sepenuhnya terkumpul, A.S. melakukan serangan militer besar-besaran ke Afghanistan untuk membunuh bin Laden dan menumbangkan rezim Taliban yang melindungi bin Laden. Dewi Fortuna Anwar, Tatanan Dunia Baru 21 Tindakan pembalasan yang dilakukan A.S. terhadap rezim Taliban di Afghanistan, untuk kejahatan yang dilakukan oleh individu-individu dari negara lain yang tidak berkaitan langsung dengan rezim tersebut, melangkah jauh dari perang pembalasan yang diperbolehkan oleh Piagam PBB ketika menghadapi agresi militer dari negara lain. (Sebagian besar pelaku penyerangan tanggal 11 September 2001 adalah warga negara Arab Saudi). Namun hal ini tampaknya tidak dipedulikan oleh pemerintahan Bush, walaupun aksi militer A.S. di Afghanistan mendapat banyak kecaman internasional. A.S. berdalih bahwa rezim Taliban membiarkan wilayah Afghanistan dipakai oleh kelompok Al-Qaeda yang tetap merupakan ancaman bagi A.S., sehingga untuk menghancurkan Al-Qaeda dan mencegah aksi terror selanjutnya rezim Talibanpun harus ikut dihancurkan. Dalam perang melawan teroris yang dicanangkan A.S. negara yang membiarkan kelompok teroris berada di wilayahnya tampaknya juga dianggap sebagai teroris atau pendukung terorisme sehingga perlu diperangi, sebelum ancaman itu menjadi kenyataan. Pandangan pemerintah A.S. tentang ancaman yang dihadapi negara tersebut dan strategi menghadapinya semakin dikembangkan melalui apa yang kemudian dikenal sebagai Doktrin Bush. Doktrin Bush pertama kali disampaikan pada tanggal 1 Juni 2002, dalam pidato wisuda mahasiswa akademi militer West Point. Dalam pidato tersebut Bush menjelaskan bahwa ancaman masa depan datang dari para teroris serta dari para diktator yang mengembangkan senjata pemusnah massal yang dapat diberikan kepada para teroris. Untuk menghadapi ancaman tersebut strategi deterrence seperti waktu menghadapi ancaman Blok Komunis selama Perang Dingin tidak lagi sesuai. Sebaliknya A.S. harus mengantisipasi ancaman tersebut dan melakukan tindakan pre-emption, yaitu menyerang sebelum ancaman tersebut menjadi kenyataan. Pemikiran Bush dapat dilihat dari kutipan-kutipan pidatonya sebagai berikut: “We cannot defend America and our friends by hoping for the best. We cannot put our faiths in the word of tyrants who solemnly sign nonproliferation treaties and then systematically break them. If we wait for threats to fully materialize we will have waited too long”. (Kita tidak dapat mempertahankan Amerika dan rekan-rekan kita dengan mengharap yang terbaik. Kita tidak dapat meletakkan kepercayaan kita pada kata-kata tiran yang menandatangani perjanjian non-proliferasi namun secara sistematis melanggar perjanjian tersebut. Kalau kita menunggu ancaman untuk menjadi kenyataan kita sudah terlambat). Demokrasi & HAM Vol. 3, No. 2, Mei-September 2003 22 Berikutnya Bush mengatakan bahwa “.. the war on terror will not be won on the defensive. We must take the battle to the enemy, disrupt his plans and confront the worst threats before they emerge”. (Perang melawan teror tidak dapat dimenangkan secara defensif. Kita harus membawa pertempuran kepada musuh, ganggu rencananya dan hadapi tantangan terburuk sebelum ia menjelma). Bush juga menjelaskan bahwa tentara A.S. harus siap menyerang setiap saat di pelosok dunia manapun: “A military that must be ready to strike at a moment’s notice in any dark corner of the world”.13 Pandangan Bush ini, yang merupakan kelanjutan dari doktrin preemptive strike yang dikemukakan Pentagon tahun 1992, samasekali tidak lagi mengindahkan Piagam PBB dan hukum internasional lainnya tentang perang yang sah. Doktrin ini membenarkan tindakan agresi terhadap negara lain hanya berdasarkan kecurigaan A.S. terhadap niat atau kemampuan yang dimiliki negara tersebut. Tentara A.S. dapat melakukan serangan di mana saja, kapan saja, melawan siapa saja sesuai persepsi ancaman Washington, tanpa memerlukan mandat PBB ataupun dukungan internasional. Perang melawan terorisme merupakan perang tanpa mengenal batas waktu ataupun batas wilayah. Serangan A.S. terhadap Irak untuk menggulingkan rezim Saddam Hussein, kendati seperti telah disinggung sebelumnya tidak terdapat bukti yang kuat bahwa Saddam Hussein memiliki kaitan dengan Al-Qaeda, merupakan realisasi Doktrin Bush. Seperti diketahui keinginan tokohtokoh konservatif A.S. untuk menyingkirkan Saddam Hussein, yang dicurigai telah mengembangkan senjata pemusnah massal sehingga mengancam Isreal dan kepentingan A.S. di Timur Tengah secara keseluruhan, telah cukup lama tercetus. Misalnya, pada tahun 1998 di bawah bendera Project for the New American Century (PNAC) 18 orang tokoh konservatif menulis surat pada Presiden Clinton untuk mendongkel Saddam Hussein dari kekuasaan.14 10 dari 18 tokoh tersebut kini duduk dalam pemerintahan Bush, dan setelah terjadi serangan teroris di New York yang akhirnya melahirkan Doktrin Bush, keinginan untuk menggulingkan Saddam mendapat pembenaran baru. 13. Commencement Speech given by President George w. Bush to the U.S. Military Academy’s 2002 graduating class at West Point. The speech was given on June 1, 2002, at West Point New York. JINSA Online, June 4, 2002. 14. Bara Hasibuan op.cit. Dewi Fortuna Anwar, Tatanan Dunia Baru 23 Lebih jauh lagi Doktrin Bush menyatakan bahwa A.S. tidak saja akan memerangi setiap potensi ancaman yang mungkin mucul, tetapi juga akan secara aktif mendukung “freedom” atau kebebasan di seluruh dunia. Menurut seorang pengamat, pidato Bush di West Point merupakan pidato bersejarah yang meletakkan dasar bagi lahirnya tatanan dunia baru dengan A.S. sebagai pusatnya dan “kebebasan” sebagai tujuannya.15 Menggulingkan rezim Taliban di Afghanistan dan rezim Saddam Hussein di Irak untuk membuka jalan terbentuknya pemerintahan yang demokratis merupakan wujud dari Doktrin Bush yang oleh seorang pengamat juga disebut sebagai “liberty doctrine”. Berbeda dengan pemerintahan Clinton sebelumnya yang juga mengupayakan penyebaran demokrasi melalui dukungan pada gerakangerakan pro-demokrasi dan tekanan ekonomi atau diplomatik pada rezim yang tidak demokratis, Bush memaksakan demokrasi pada negara-negara sasaran melalui intervensi militer A.S. secara langsung dan mengubah tatanan politik di negara tersebut di bawah komando Washington. Presiden Bush yakin A.S. berada pada posisi yang benar dan merasa berkewajiban untuk menyebar kebenaran serta melawan kekuatan jahat (evil) secara unilateral di seluruh penjuru dunia dengan menggunakan kekuatan militer A.S. yang tidak tertandingi, dan tidak boleh ditandingi. Seperti dikatakannya: “America has, and intends to keep, military strengths beyond challenge—thereby making the destabilizing arms races of other eras pointless, and limiting rivalries to trade and other pursuits of peace”.16 Amerika di bawah Presiden Bush merupakan misionaris bersenjata yang percaya bahwa A.S. ditakdirkan untuk memimpin dunia demi kebaikan dunia itu sendiri. Tantangan terhadap hegemoni Amerika Serikat Sejarah berulang kali menunjukkan bahwa dominasi suatu negara terhadap negara lain tidak dapat bertahan selama-lamanya. Dominasi yang berlebihan selalu menimbulkan perlawanan dan akan muncul kekuatan-kekuatan baru yang menyaingi. Hegemoni A.S. dengan kebijakan unilateralisme yang kontroversial baru berlangsung dalam dua 15. Tod Lindberg, “The War on Terror: The Bush Doctrine”. Hoover Digest, 2002 no. 4, Fall Issue. 16. Pidato di West Point, ibid. 24 Demokrasi & HAM Vol. 3, No. 2, Mei-September 2003 tahun terakhir, namun perlawanan terhadap ketidakseimbangan kekuatan ini sudah mulai tampak. Kecaman terhadap unilateralisme tidak saja datang dari negara-negara yang memang selama ini kritis atau jauh dari A.S., tetapi juga dari sebagian sekutunya. Seperti telah disinggung sebelumnya, kepemimpinan A.S. yang telah berlangsung sejak Perang Dunia II berakhir relatif dapat diterima secara luas karena kepemimpinan tersebut berlangsung dalam kerangka sistem multilateral. Dengan demikian negara-negara lain, khususnya negaranegara besar lainnya, tetap dilibatkan dalam setiap kebijakan internasional yang diambil. Namun setelah pemerintahan Bush menunjukkan bahwa ia hanya peduli pada kepentingan nasional A.S. dan menjalankan kebijakan-kebijakan unilateral dalam interaksi internasional, A.S. mulai dilihat sebagai ancaman oleh sebagian sekutunya sendiri. Keinginan A.S. untuk menyerang Irak tanpa mengindahkan upaya PBB yang berusaha mengatasi krisis Irak melalui cara damai mendapat tantangan dari sebagian besar negara di dunia, terutama dari Perancis dan Jerman yang merupakan sekutu A.S. dalam NATO (North Atlantic Treaty-Pakta Pertahanan Atlantik Utara). RRC dan Rusia, yang merupakan anggota Dewan Keamanan PBB juga menentang serangan militer A.S. ke Irak. Penolakan sebagian besar negara di dunia terhadap keinginan A.S. melancarkan aksi militer ke Irak bukanlah karena mereka mendukung Saddam Hussein, namun karena mereka menilai bahwa tidak ada alasan kuat untuk membenarkan penyerangan. Tim inspeksi senjata PBB masih melaksanakan tugas mereka dan belum menemukan bukti-bukti bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal seperti yang dituduhkan. Di samping itu penggulingan pemerintahan suatu negara yang berdaulat oleh negara lain tidak dibenarkan oleh Piagam PBB. Dengan kata lain negara-negara yang menentang sikap A.S. ingin tetap berpegang pada hukum internasional yang berlaku, dan tetap menempatkan PBB sebagai satu-satunya kekuatan internasional yang berwenang untuk menggelar aksi militer secara internasional. Tindakan A.S. telah menimbulkan perpecahan di dalam NATO. Hal ini jelas menunjukan ketidakpuasan sebagian anggota NATO, khususnya Perancis dan Jerman yang merupakan dua negara terbesar dalam Uni Eropa, atas tindakan sewenang-wenang A.S. yang sama sekali tidak mempedulikan pendapat pihak lain. A.S. telah memutuskan untuk menyerang Irak dan terserah negara lain untuk mendukungnya atau tidak. Akhirnya A.S. hanya didukung oleh sedikit negara yang merupakan sekutunya yang paling setia, antara lain Britania. Hubungan Dewi Fortuna Anwar, Tatanan Dunia Baru 25 A.S. dengan negara-negara Eropa yang menentang perang, yang dijuluki Menteri Pertahanan Rumsfeld sebagai “Eropa Tua” menjadi tegang. Sikap anti A.S. meluas di Eropa, termasuk di negara-negara yang pemerintahnya mendukung perang. Terlalu dini untuk mengatakan bahwa sebagai konsekuensi dari ketidakpuasan terhadap arogansi A.S. akan segera muncul kekuatan tandingan baru. Untuk sementara waktu kekuatan A.S. tidak tertandingi, dan tidak satupun negara yang secara terbuka mengatakan hendak menyaingi A.S., namun kondisi seperti ini diyakini tidak akan berlangsung selamanya. Kendati A.S. bertekad untuk mencegah munculnya kekuatan pesaing, sistem hegemoni mengandung kelemahan dasar, yaitu ia tidak populer. Semakin kuat dan semakin dominan suatu negara, yang cenderung memunculkan sikap arogan seperti yang belakangan ini ditunjukkan A.S., maka akan semakin banyak pihak yang tidak menyukainya. Di Eropa Barat mulai muncul upaya untuk lebih mandiri dari A.S. dalam bidang pertahanan. Sebenarnya sejak lama beberapa negara, terutama Perancis, telah ingin membentuk pakta pertahanan Eropa Barat di luar NATO, namun hal tersebut sulit direalisasikan. Namun pada tanggal 29 Mei 2003 ini empat negara anggota Uni Eropa, Jerman, Perancis, Belgia dan Luksemburg penentang perang Irak mengadakan pertemuan di Brussel. Mereka sepakat untuk membentuk komando pasukan di luar NATO. Meskipun ditentang keras oleh Britania dan sebagian besar anggota Uni Eropa lainnya, usul keempat negara tersebut dikabarkan mendapat dukungan dari Rusia dan Yunani.17 Apabila tiga negara besar, Perancis, Jerman dan Rusia memutuskan untuk membangun kekuatan militer tandingan jelas mereka berpotensi mampu mengimbangi kekuatan A.S., mengingat kemampuan ekonomi dan teknologi yang mereka miliki. Sebagian besar persenjataan Uni Soviet diwarisi oleh Rusia, sementara Perancis dan Jerman merupakan dua negara besar yang memiliki sejarah kebesaran militer di masa lalu. Di lingkungan Asia Pasifik juga ada negara besar yang berpotensi menjadi pesaing A.S. dalam jangka menengah dan panjang. Baik dilihat dari pertumbuhan ekonomi maupun moder nisasi militer yang dilakukannya, RRC diyakini akan tampil sebagai kekuatan global dalam 17. Koran Tempo, “Rusia Isyaratkan Dukung Pakta Pertahanan Eropa”. 2 Mei 2003. Demokrasi & HAM Vol. 3, No. 2, Mei-September 2003 26 waktu yang tidak terlalu lama. RRC tentu tidak akan dapat menerima dalam jangka panjang suatu tatanan dunia yang sepenuhnya dikontrol dan dibentuk oleh A.S., yang tidak memberi tempat yang sejajar pada negara-negara besar lainnya. Menurut Kenneth Waltz, ahli politik internasional beraliran realist dari A.S., Amerika Serikat sekarang sedang berada pada puncak kejayaan yang tidak akan dapat dipertahankannya terlalu lama. Pertama, penduduk A.S. hanya 276 juta jiwa dari 6 milyar jiwa, atau 5 % dari total penduduk dunia. Kemampuan fisik dan kemauan politik A.S. tidak akan mampu menanggung beban internasional yang berat seperti sekarang ini untuk selamanya. Kedua, negara-negara lain tidak akan puas ditempatkan dalam gerbong belakang. Baik teman maupun musuh akan beraksi, sebagaimana negeri-negeri sejak dahulu telah beraksi terhadap ancaman predominasi: mereka akan memperbaiki perimbangan kekuatan.18 Di samping akan muncul upaya perimbangan kekuatan terhadap dominasi A.S., betapapun A.S. akan mencoba mencegah munculnya perlombaan senjata baru, sebagian besar masyarakat internasional juga akan tetap berjuang untuk memperkuat sistem multilateralisme yang selama ini sudah berjalan dengan cukup baik. Pertentangan A.S. dan Eropa belakangan ini bukanlah karena persaingan ideologis atau karena mereka bermusuhan. Perselisihan terjadi terutama karena pandangan yang dianut A.S. tentang cara terbaik mengatur hubungan internasional berbeda dengan pendekatan negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Sebagai satu-satunya negara adidaya A.S. mampu dan lebih suka bertindak secara unilateral, sementara Uni Eropa adalah organisasi multilateral di mana setiap anggota dituntut untuk bertindak secara multilateral, berdasarkan keputusan yang dibuat secara bersama, untuk setiap keputusan.19 Walaupun A.S. dan Uni Eropa memiliki kemampuan ekonomi yang relatif sama, visi dan bentuk kekuasaan mereka berbeda. A.S. merupakan kekuatan militer yang tetap menganggap bahwa berbagai konflik di dunia dapat diselesaikan secara militer. Sebaliknya, negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa telah berupaya menyingkirkan kemungkinan 18. Waltz, op.cit. hal-55-56. 19. Anne-Marie Slaughter, “The Future of Intrenational Law: Ending the U.S.Europe Divide”. Crimes of War Project.- http://www.crimesofwar.org/sept-mag/septslaughter-printer.html. Dewi Fortuna Anwar, Tatanan Dunia Baru 27 ancaman perang melalui berbagai per janjian dan kerjasama internasional. Setiap pertikaian diupayakan untuk diselesaikan melalui institusi-institusi sipil, misalnya melalui negosiasi atau melalui proses hukum regional atau internasional. Bukanlah suatu kebetulan bahwa A.S. yang gemar melancarkan aksi militer di luar negeri tidak pernah mengalami perang di dalam negeri sejak Perang Saudara pada abad ke19, sementara negara-negara Eropa Barat yang berkali-kali hancur oleh perang akhirnya memutuskan untuk mengedepankan cara-cara damai. Seperti dikatakan seorang pengamat, “the EU is a civilian superpower, wielding civilian power in contrast to the U.S.’s military power’. 20 Menarik untuk disimak bahwa kekuatan yang berpotensi dapat mengubah tatanan global yang sekarang didominasi Amerika Serikat adalah Eropa Barat yang merupakan sekutu terdekat A.S. dalam 50 tahun terakhir. Perseteruan antara A.S. dan EU mengenai ICC (International Criminal Court) secara jelas menunjukkan perbedaan pandangan antara keduanya mengenai hukum internasional dan jurisdiksinya. A.S. mengancam akan memutuskan bantuan militer pada negara-negara yang menolak menandatangi perjanjian bilateral dengannya untuk menjamin bahwa tentara A.S. yang berada di negara yang bersangkutan terbebas dari jurisdiksi ICC. Sebaliknya EU mengingatkan negara-negara yang hendak bergabung masuk EU, misalnya Turki dan Turkmenistan, untuk tidak menandatangani perjanjian tersebut apabila mereka tetap ingin diterima di dalam EU.21 Bagaimana dengan nasib PBB ke depan? Tindakan unilateral A.S. dalam menyerang Irak jelas telah melecehkan dan memarjinalkan peran PBB. PBB menunjukkan ketidakberdayaannya ketika berhadapan dengan kemauan keras A.S. Namun walaupun A.S. berusaha menunjukkan bahwa PBB tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah internasional, terutama apabila diperlukan suatu tindakan militer secara cepat, hal ini tidak mengurangi otoritas yang dimiliki PBB. Serangan A.S. ke Irak tidak memiliki legitimasi karena tidak didukung oleh PBB. A.S. pun sesungguhnya menyadari hal ini, sehingga Washington berupaya untuk meyakinkan PBB agar mengeluarkan resolusi yang melegitimasi serangan atas Irak tersebut. Menteri Luar Negeri Colin Powell secara khusus 20. Andrew Moravcsik, “The Quiet Superpower”. Newsweek, June 17, 2002. 21. Slaughter, ibid. 28 Demokrasi & HAM Vol. 3, No. 2, Mei-September 2003 menyampaikan presentasi di depan Dewan Keamanan PBB untuk menunjukkan bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal. 22 Demonstrasi besar-besaran di seluruh dunia menentang invasi A.S. ke Irak terutama disebabkan oleh pandangan bahwa tindakan A.S. tersebut tidak sah karena tidak mendapat mandat PBB. Tindakan unilateralisme A.S. justru meningkatkan tekad sebagian besar masyarakat internasional untuk memperkuat PBB dan proses multilateral. Misalnya, masyarakat internasional menuntut agar pembangunan Irak setelah perang usai harus dilakukan oleh PBB, bukan oleh A.S. semata. Tiga pemimpin Eropa yang menentang perang, Presiden Vladimir Putin dari Rusia, Presiden Jacques Chirac dari Perancis dan Kanselir Gerhard Schroder dari Jerman mengadakan pertemuan di St. Petersburg pada tanggal 11 April 2003, beberapa hari setelah pasukan A.S. memasuki Baghdad. Dalam pertemuan tersebut ketiga pemimpin menegaskan bahwa PBB harus memainkan peran utama dalam rekonstruksi Irak untuk mencegah kolonialisme baru di negeri tersebut. Perdana Menteri Britania, Tony Blair, pendukung utama Bush yang turut mengirim pasukan ke Irak, juga menuntut agar PBB lah yang harus berperan utama di Irak pasca-perang.23 Seperti dikatakan Kenneth Waltz, tidak saja musuh tetapi teman pun tidak suka diperlakukan sebagai warga kelas dua oleh suatu negara adidaya. Tindakan unilateralisme A.S. di Irak mendapat dukungan dari sebagian negara seperti Britania karena komitmen persekutuan atau karena mereka yakin akan kebenaran tindakan tersebut. Namun upaya A.S. untuk menguasai Irak secara ekonomi pasca-perang, antara lain dengan hanya memberikan kontrak-kontrak kerja bernilai besar kepada perusahaanperusahaan A.S., menimbulkan ketidakpuasan luas dari negara-negara besar lainnya, termasuk sekutu-sekutu setia A.S. sendiri. Apabila peranan utama dimainkan oleh PBB maka pembangunan Irak tentu akan melibatkan banyak negara. Dengan demikian tantangan atas unilateralisme A.S. tidak saja disebabkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan tindakan militer atau karena ia mangabaikan hukum-hukum internasional, tetapi juga karena kepentingan ekonomi negara-negara lain yang turut dirugikan. 22. Ramesh Thakur and Andrew Mack, “The United nations. More relevant now than ever”. Special to the Japan Times. Sunday, march 23, 2003. 23. The Moscow Times.com, “Petersburg Summit Pushes for UN Role”. April, 14, 2003. ANALISIS Pasca Agresi Amerika ke Irak Riza Sihbudi1 Pengantar Seperti sudah diperkirakan sebelumnya, pada 21 Maret 2003, Amerika Serikat (AS) akhirnya memang melancarkan agresi paling brutal terhadap rakyat dan negara Irak tanpa dikutuk—apalagi dicegah—oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). AS—yang didukung sepenuhnya oleh Inggris, Australia dan Spanyol—sama sekali tidak menghiraukan kecaman dan keberatan dari berbagai negara yang anti-perang. Sejak awal Presiden AS, George W. Bush, memang tidak mempunyai opsi lain selain mengumandangkan genderang perang. AS bahkan tidak perlu menunggu hasil sidang DK (Dewan Keamanan) PBB yang semula hendak memperdebatkan rancangan resolusi kedua yang mereka buat bersama Inggris. Pasalnya, Prancis dan Rusia yang memiliki hak veto di DK PBB sudah dipastikan akan menjegal rancangan resolusi yang memberikan wewenang penggunaan kekuatan militer terhadap Irak itu. Agresi sudah dilancarkan dan hanya dalam waktu tiga pekan negara Irak pun sudah sepenuhnya berada di bawah pendudukan para serdadu kolonial AS dan kawan-kawannya. Bagaimana pun kekuatan militer Irak tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan militer para agresor (AS). Apalagi sebelum diduduki, Irak sudah terlebih dulu dilucuti oleh PBB. 1. Ahli Peneliti Utama dan Kepala Bidang Perkembangan Politik Internasional pada Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI); Dosen Pasca Sarjana Universitas Indonesia (UI) Program Kajian Timur Tengah dan Islam; Ketua Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES) Jakarta; dan, Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI). 30 Demokrasi & HAM Vol. 3, No. 2, Mei-September 2003 Skenario utama AS pun sudah jelas yaitu membentuk pemerintahan boneka di Irak. Tujuan utamanya, menguasai ladang minyak Irak. Sampai sekarang komoditas minyak memang belum bisa digantikan oleh energi lain untuk kebutuhan industri. Jadi, penguasaan minyak sangat strategis buat AS. Apalagi, cadangan minyak di Irak merupakan yang terbesar setelah Arab Saudi. Di samping itu, Bush sendiri seorang pengusaha minyak. Dengan menguasai Irak, AS juga mendapatkan pijakan baru di kawasan Teluk Parsi, karena setelah Revolusi Islam di Iran (1979), AS kehilangan basis utamanya di kawasan ini. Bush dan para anteknya menjadikan para pembelot Irak untuk berkuasa di Baghdad untuk menggantikan rezim Saddam Hussein, kendati kekuatan kelompok oposisi di Irak—di luar suku Kurdi dan kaum Muslim Syiah—sebenarnya tidak begitu kuat. Mereka bahkan cenderung terpecah-pecah, karena tidak adanya figur yang mampu menjadi tokoh pemersatu gerakan anti-Saddam. Yang menjadi pertanyaan, apa sebenarnya ambisi AS di bawah Bush untuk menduduki Irak, dan apa dampak agresi AS ke Irak terhadap kawasan Timur Tengah? Tekanan Faksi Pro-Israel Pada awal Januari 2003, Pemerintah Irak menyatakan menerima Resolusi DK PBB No. 1441, 2 dan UNMOVIC (United Nations Monitoring, Verification and Inspection Comission) yaitu tim inspeksi senjata PBB yang diketuai Hans Blix, pun sudah melakukan tugasnya, kendati waktu itu mereka berharap dapat diberikan waktu tambahan sekitar tiga bulan lagi. Gelombang aksi anti-perang yang digerakkan kaum aktivis pro-perdamaian pun melanda di berbagai kawasan, termasuk di negara-negara Barat yang selama ini dikenal sebagai sekutu dekat AS, seperti Inggris dan Australia. Bahkan demo anti-perang juga marak di AS sendiri. Namun, kesemuanya itu tidak menyurutkan sedikit pun ambisi George W. Bush untuk melancarkan aksi militer terhadap Irak, baik dengan ataupun tanpa persetujuan PBB, dengan target utama menggulingkan Presiden Irak Saddam Hussein guna menguasai minyak 2. Resolusi 1441 disahkan pada 8 November 2002, yang isinya antara lain menuntut Irak untuk mengijinkan dan memberikan akses sepenuhnya kepada UNMOVIC dan IAEA untuk meneliti segala hal yang berkaitan dengan persenjataan yang dimiliki Irak. Riza Sihbudi, Pasca Agresi Amerika ke Irak 31 Irak serta melayani kepentingan Israel. Jika memperhatikan pernyataanpernyataan Bush (dan para pejabat tinggi AS lainnya) baik sebelum maupun setelah keluarnya Resolusi 1441, serta persiapan yang makin intensif dari angkatan bersenjata AS sejak Januari 2003,3 maka jelas sekali bahwa Bush memang sangat berhasrat menyerang dan menduduki Irak. Sebelum keluarnya resolusi DK PBB tersebut, Bush tidak hanya menuduh Saddam Hussein sebagai “ancaman bagi perdamaian dunia” karena terus mengembangkan senjata-senjata pemusnah massal, namun Saddam pun dituduh berkolaborasi dengan kaum “teroris” internasional, khususnya Osama Bin Laden. Bahkan Saddam juga didakwa terlibat dalam kasus pemboman di Bali. Suatu tuduhan yang bagi banyak orang, sangat tidak masuk akal. Dalam pidato kenegaraannya (“state of the union”), 29 Januari 2003, Bush memang tidak secara eksplisit menyatakan deklarasi perang terhadap Irak. Namun, secara implisit keinginan Bush untuk sesegera mungkin menyerang Irak dan menggulingkan Presiden Saddam Hussein, tetap menggebu. Bagi Bush tidak ada opsi lain selain perang dan perang, kendati laporan hasil tim UNMOVIC maupun Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) sudah menyatakan tidak menemukan bukti-bukti yang otentik dan akurat (otentik belum tentu akurat, dan sebaliknya) perihal kepemilikan senjata pemusnah massal oleh Irak. Bush juga menganggap sepi terhadap makin maraknya aksi-aksi anti-perang di berbagai belahan dunia, termasuk di AS sendiri. Pada awal Maret 2003, AS dan Inggris mengultimatum Irak, jika sampai 17 Maret 2003 belum menghancurkan senjata pemusnah massalnya, negeri Saddam Hussein ini akan diserang habis-habisan. Waktu itu Gedung Putih mengaku menemukan bukti-bukti baru bahwa Irak belum menghancurkan senjata pemusnah massalnya.4 Sebelumnya, dalam konferensi pers yang diadakan pada 6 Maret 2003, Bush kembali menegaskan niatnya untuk menginvasi Irak dengan atau tanpa persetujuan DK PBB. 3. Hingga saat itu AS telah menempatkan 250.000 tentara, dan 215.000 di antaranya sudah siap tempur. Kekuatan pasukan AS akan mencapai 310.000 personel. Qatar menjadi pusat komando dalam serangan AS ke Irak, sedangkan Kuwait saat itu sudah menampung hampir 140.000 personel militer AS dan Inggris. 4. CNN.com (10 Maret 2003). 32 Demokrasi & HAM Vol. 3, No. 2, Mei-September 2003 Padahal dalam waktu yang sama, baik Ketua UNMOVIC, Hans Blix, maupun Direktur IAEA, Mohammed ElBaradei, dengan gamblang sudah mengemukakan bahwa tidak diketemukannya bukti-bukti yang konkrit perihal pelanggaran Irak terhadap Resolusi DK PBB No. 1441. ElBaradei bahkan mengatakan tudingan AS dan Inggris bahwa Irak berusaha mendapatkan uranium dari Niger adalah tidak benar. Tudingan itu bisa dipastikan hanya didasarkan pada dokumen-dokumen palsu yang direkayasa oleh para agen dinas intelijen. Oleh sebab itu, suara keras yang menentang rencana serangan AS ke Irak pun kian meluas. Dalam komunike yang dikeluarkan pada akhir Konferensi Tingkat Tinggi darurat di Doha, Qatar, 5 Maret 2003, negaranegara anggota OKI atau OIC (Organization of Islamic Conference) satu suara dalam menolak serangan AS. Ke-57 negara anggota OKI juga menolak setiap ancaman terhadap keamanan negara Islam mana pun. Suara OKI ini sejalan dengan hasil KTT Liga Arab maupun Gerakan Nonblok (GNB) sebelumnya. Menyinggung ancaman AS untuk menggulingkan Saddam dan “menata kembali” peta Timur Tengah, para pemimpin OKI dengan tegas menentang setiap usaha memaksakan perubahan di kawasan ini dan menentang campur tangan pihak luar terhadap urusan internal mereka. Dalam pertemuan darurat para Menlu Prancis, Rusia, dan Jerman di Paris, mereka juga secara tegas menolak rencana serangan militer ke Irak. Selain menolak perang, Prancis bersama Rusia menyatakan siap menggunakan hak veto. “Kami tidak akan meluluskan kerangka resolusi yang merencanakan penggunaan kekuatan senjata. Rusia dan Prancis sebagai anggota tetap DK PBB, sepenuhnya akan mempertanggung– jawabkan hal tersebut,” kata Menlu Perancis Dominique de Villepin dalam jumpa pers bersama Menlu Jerman Joschka Fischer dan Menlu Rusia Igor Ivanov. Pemimpin umat Katolik dunia, Paus Yohanes Paulus II, pun kembali mendesak seluruh pemimpin dunia untuk menghindari perang. Sementara itu, para aktivis perdamaian mulai berdatangan ke Irak untuk menjadi tameng manusia dalam menghadapi serangan AS. Akan tetapi, gerakan perlawanan global tidak mampu mengubah ambisi Bush menyerang Irak. Para pejabat AS menyatakan, serangan terpaksa ditunda (dari rencana semula, 17 Maret 2003), karena waktu itu Turki tidak mengizinkan penggunaan pangkalan militernya. Dalam sebuah pemungutan suara, parlemen Turki menolak penempatan 62.000 tentara AS di wilayahnya. Untuk itu, Kementerian Luar Negeri AS Riza Sihbudi, Pasca Agresi Amerika ke Irak 33 kemudian menyarankan meningkatkan paket bantuan ekonomi kepada Turki menjadi 30 milyar dollar AS. Tawaran AS sebelumnya hanya 26 milyar dollar AS. Dan, Turki pun kemudian mengijinkan wilayahnya dijadikan sebagai pangkalan bagi serangan udara AS ke Irak.5 Bush sendiri kembali menegaskan, Saddam harus disingkirkan, kalau perlu dengan kekuatan. Pernyataan itu sekaligus memperlihatkan dendam pribadi Bush terhadap Saddam. Pernyataan Bush itu mencerminkan bahwa ambisinya untuk melancarkan agresi sama sekali tidak mengendur. Tidak ada perubahan dari posisi Bush yang tetap akan menginvansi Irak dengan atau tanpa payung PBB. Jelas sekali, Bush mendapat tekanan dari kelompok garis keras di AS yang militeristik dan sangat pro-Israel. Perang menjadi satu-satunya tujuan mereka untuk mencapai sasaran utamanya yaitu menguasai minyak Irak dan mengamankan Israel. Sebaliknya, Irak terus menarik simpati masyarakat global dengan sikapnya yang kooperatif. Irak membuka seluruh akses, termasuk ke Istana Kepresidenan, bagi UNMOVIC maupun IAEA. Menurut juru bicara PBB di Irak Yasuhiro Ueki, Irak pun kembali menghancurkan tiga rudal dan lima mesin rudal. Sebelumnya, Irak menghancurkan enam rudalnya. Sejak Februari 2003, Irak memang telah memusnahkan puluhan rudal Al-Samoud II, yang dicurigai AS dapat menjangkau Israel. Namun, semuanya itu tampaknya tidak ditanggapi oleh Bush dan para sekutunya. Ia bahkan menuding Saddam berlaku “kucing-kucingan” seraya makin memperkuat jumlah kekuatan militernya di sekitar kawasan Teluk Parsi. Jika demikian halnya, siapakah yang sebenarnya dapat diharapkan mencegah ambisi Bush untuk mengobarkan peperangan terhadap Irak? Seperti yang sudah terlihat dalam beberapa pekan terakhir sebelum 21 Maret 2003, tekanan masyarakat dunia tidak mampu mengubah sikap keras kepala Bush. Bahkan ancaman Prancis dan Rusia untuk menggunakan hak vetonya jika AS dan Inggris tetap mengajukan rancangan resolusi kedua ke DK PBB, ditanggapi Bush dengan ancaman balik untuk tetap menyerang Irak, dengan atau tanpa mandat PBB. Sebenar nya yang saat itu masih bisa diharapkan dapat menghentikan ambisi perang Bush, adalah sikap rakyat AS sendiri. 5. Kendati pemerintahannya dipimpin oleh seorang PM dari sebuah partai Islam, namun politik Turki lebih banyak ditentukan oleh kalangan militer konservatif yang sangat pro-AS. Demokrasi & HAM Vol. 3, No. 2, Mei-September 2003 34 Demonstrasi antiperang di AS yang mulai meluas—jika semakin membesar—bukan tidak mungkin mampu mempengaruhi sikap Kongres, yang berada di belakang Bush. Di Inggris posisi PM Tony Blair sempat goyah, karena 200 anggota parlemen dan 10 menteri dari Partai Buruh melancarkan “pembangkangan” terhadap Blair.6 Ini disebabkan makin kuatnya tekanan dari rakyat Inggris yang menentang perang. Hal yang sama bukan mustahil dapat terjadi juga di AS. Dan, jika ini terjadi maka benarlah apa yang tertulis dalam sebuah poster para aktivis antiperang di Eropa: Drop Bush, Not Bombs. Sayangnya, suara hati nurani sebagian rakyat AS tidak dapat mencegah ambisi perang Bush. Paling tidak, ada enam faktor yang memotivasi Bush di balik ambisi perangnya.7 Pertama, Bush menggunakan isyu “perang Irak” untuk menutupi berbagai ketidak-berhasilannya dalam mengatasi persoalan sosial-ekonomi di dalam negerinya sendiri. Ini misalnya terlihat dari salah satu slogan yang diusung para penggiat anti-perang Irak di Washington DC pada saat itu, yaitu “Money for Jobs, Not for War” (gunakan uang negara untuk menciptakan lapangan kerja, bukan untuk membiayai perang). Kedua, keinginan Bush untuk melampiaskan dendam keluarganya terhadap Saddam. Bush tidak pernah menyembunyikan kemurkaannya pada Saddam Hussein yang dituduh pernah berupaya membunuh ayahnya, Bush senior (mantan Presiden AS George Bush). Ketika membombardir Irak pada 1990-1991, Bush senior memang berhasil mengusir pasukan Irak dari Kuwait, namun ia gagal menggulingkan kekuasaan Saddam. Ironisnya, justru ia sendiri yang kemudian “terguling” dari kekuasaan karena dikalahkan oleh Bill Clinton dalam pemilihan Presiden AS tahun 1992. Kegagalan sang bapak itulah yang di kemudian hari hendak ditebus oleh sang anak. Ketiga, Bush ingin menutupi kegagalannya dalam memburu Osama bin Laden dan Mullah Umar di Afghanistan. Sekalipun ia sukses meluluh-lantakkan Afghanistan—dengan mengorbankan ribuan nyawa warga sipil negeri ini—namun Bush gagal total dalam mengejar target utamanya, yaitu menangkap (hidup atau mati) pemimpin Al-Qaidah, Osama bin Laden, yang dituding sebagai pelaku utama serangan yang 6. CNN.com (9 Maret 2003). 7. Lihat juga, Tim ISMES, Saddam Melawan Amerika (Jakarta: Pensil 324, 2003), hlm. 33-34. Riza Sihbudi, Pasca Agresi Amerika ke Irak 35 amat fenomenal terhadap WTC dan Pentagon pada 11 September 2001, serta pemimpin Taliban, Mullah Umar, yang menjadi sekutu utama Osama. Keempat, terinspirasi oleh keberhasilannya dalam menghancurkan rezim Taliban dan menciptakan rezim boneka di Afghanistan, Bush berusaha melakukan hal yang sama di Irak. Oleh sebab itu setelah menggulingkan Taliban, obsesi Bush berikutnya adalah menggulingkan Saddam Hussein dan mendirikan rezim boneka di Irak yang dapat didikte oleh Washington. Tujuannya, tidak lain, untuk menguasai minyak Irak. Seperti diketahui, Irak menjadi salah satu negara yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Menguasai minyak Irak sangat berarti baik bagi AS maupun Bush pribadi, yang keluarganya memiliki bisnis minyak. Saddam, yang di masa lalu, dipertahankan oleh AS untuk dijadikan sebagai “monster” bagi negara-negara kaya minyak di kawasan Teluk Parsi agar mereka selalu berlindung di bawah payung AS, dianggap sudah tidak memiliki arti strategis lagi bagi Bush. Kelima, seperti dalam kasus kampanye anti-terorisme yang dikembangkan AS pasca-tragedi 11 September 2001, dalam kasus Irak pun tampak jelas kuatnya pengaruh faksi garis keras di lingkaran elite politik Gedung Putih. Mereka, yang dimotori Wapres Dick Cheney, Menhan Donald Rumsfeld, Deputi Menhan Paul Wolfowitz, serta Penasehat Keamanan Nasional (NSC) Condoleezza Rice, memang dikenal sebagai kelompok “neo-konservatif ” yang selalu mengedepankan pendekatan pragmatis dan sangat militeristis.8 Yang ada di benak mereka hanya perang dan perang. Sementara persoalan hak-hak asasi manusia dan demokrasi justru dikesampingkan. Tidak mengherankan, jika seorang Nelson Mandela (mantan Presiden Afrika Selatan) menuduh AS di bawah Bush sebagai negara yang sama sekali tidak memiliki sopan santun dalam pergaulan internasional. Keenam, selain berwatak militeristis, mereka juga dikenal sangat pro-Israel. Oleh karena itu, ambisi Bush untuk melucuti senjata Irak 8. Dalam beberapa hal, kelompok ini sangat dipengaruhi oleh kalangan fundamentalis Protestan. Ini antara lain dikemukakan ahli sosial demokrat dari Jerman, Thomas Meyer, dalam diskusi bertema “Perang dan Fundamentalisme” di Jakarta, 8 April 2003. Pandangan tersebut didasarkan pada dukungan untuk Bush yang berasal dari para fundamentalis Protestan yang terorganisir baik dan memiliki suara yang banyak. “Yang paling penting kaum fundamentalis di Amerika mencakup 40 persen jumlah pemilih,” kata Thomas Meyer. “George W. Bush Beraliran Politik Fundamentalis Halus”, Kompas (10 April 2003). 36 Demokrasi & HAM Vol. 3, No. 2, Mei-September 2003 juga dimaksudkan untuk mengeliminir ancaman militer Arab terhadap Israel. Irak adalah satu-satunya negara Arab yang pernah “mengirim” rudal Scud ke Israel sewaktu berlangsung Perang Kuwait (1990-1991). Memang ini sudah menjadi kebijakan dasar AS yang tidak akan membiarkan negara Arab manapun memiliki kekuatan militer yang menyamai, apalagi melebihi, kekuatan militer Israel. Di sisi lain, dengan mengobarkan perang terhadap Irak, Bush dan para pendukungnya berharap dunia internasional akan mengalihkan perhatian dari kekejaman dan kebiadaban yang terus-menerus dilakukan rezim Israel di bawah PM Ariel Sharon terhadap warga sipil Palestina. Memang, ada yang mengaitkan ambisi Bush ini dengan dikembangkannya doktrin pre-emptive strike yang dianut AS pasca Peristiwa 11 September 2001. Inti dari doktrin ini adalah—mirip “doktrin” di dunia sepakbola—”pertahanan yang baik adalah menyerang.” Artinya AS harus melancarkan serangan terlebih dulu terhadap siapa atau negara mana pun yang oleh AS dipersepsikan potensial dapat menjadi ancaman bagi kepentingan nasional AS. Selain itu, AS secara hitam-putih “membagi” dunia ini hanya menjadi dua yaitu “kami” atau “mereka” yang kadangkala dikenal dengan prinsip “either or” (“either you are with us or with our enemy”), dan yang dimaksud dengan “our enemy” oleh AS adalah kaum “teroris” internasional. Jadi, siapa pun yang tidak mau memerangi atau membantu AS dalam memerangi kaum “teroris”— apalagi yang dicurigai/dituduh mempunyai kaitan dengan kelompok “teroris” internasional—maka mereka bisa dianggap sebagai musuh AS, dan dengan sendirinya “halal” untuk diperangi. Celakanya, AS bebas menafsirkan siapa saja yang berhak dikategorikan sebagai “teroris”. Namun, dari faktor-faktor yang mendorong terjadinya agresi AS ke Irak tersebut, yang paling kuat adalah kuatnya tekanan faksi pro-Israel di lingkaran pemerintahan Bush. Mereka tidak hanya menghendaki disingkirkannya Saddam Hussein yang dianggap dapat membahayakan keamanan Israel, melainkan juga menginginkan “jatah” dari minyak Irak pasca-Saddam. Jay Garner, pensiunan jenderal AS, yang ditunjuk Bush untuk menjadi “penguasa sementara” di Irak, misalnya, dikenal sebagai salah seorang arsitek sistem pertahanan rudal Arrow di Israel. Ia juga punya kaitan erat dengan The Jewish Institute for National Security Affairs, salah satu kelompok lobi Yahudi AS yang mendukung penuh kebijakan garis keras rezim PM Israel, Ariel Sharon. Oleh sebab itu, bisa dimengerti jika sasaran AS berikutnya, setelah Irak, adalah Suriah dan Iran, dua negara Timur Tengah yang masih menolak perdamaian dengan Israel. Riza Sihbudi, Pasca Agresi Amerika ke Irak 37 Perhitungan Ekonomi dan Bisnis Bush berhasil mewujudkan ambisinya dengan melancarkan agresi terhadap Irak dan mendongkel Presiden Saddam Hussein dari kekuasaannya. Namun, agresi itu pada hakekatnya mencerminkan terkuaknya kebohongan liberalisme, kapitalisme dan demokrasi, yang selalu diagung-agungkan oleh AS serta para sekutu dan simpatisannya. Memang sangat ironis, ketika dunia mengaku memasuki era yang modern dan beradab, yang terjadi justru suatu perilaku sangat biadab dan barbar9 yang dilakukan oleh negara kuat yang mengaku sebagai pendekar hak-hak asasi manusia dan demokrasi terhadap negara yang lemah. Yang lebih ironis lagi, Bush—yang oleh Pemimpin Republik Islam Iran Ayatullah Ali Khamenei dijuluki sebagai penganut setia “Hitlerisme”—mengatasnamakan “perdamaian dan kebebasan” dalam melancarkan agresinya ke Irak. Dunia hanya bisa terperangah dan geram, tapi tak bisa berbuat apa-apa menyaksikan kebiadaban Bush dan para anteknya. Setelah berakhirnya era Perang Dingin yang ditandai dengan runtuhnya komunisme Uni Soviet dan Eropa Timur, Francis Fukuyama10 menyebut abad ini sebagai era kemenangan gemilang demokrasi dan liberalisme. Tapi, barbarisme yang dipertontonkan Bush dan para sekutunya terhadap rakyat Irak, tampaknya telah memporak-porandakan tesis Fukuyama. Kini, demokrasi dan liberalisme macam apa yang hendak dibanggakan, jika penguasa dunia seperti AS di bawah Bush dapat berbuat semena-mena dengan menebarkan kebohongan dan kemunafikan?11 Dulu, Presiden AS Ronald Reagan pernah menjuluki Uni Soviet sebagai “kerajaan setan” lantaran negara adidaya komunis itu 9. Menurut seorang Rohaniwan asal Malang, Benny Susetyo Pr. (dalam artikelnya, “Neo-Barbarisme dan Matinya Demokrasi,” Kompas, 8 April 2003), “Barbarisme yang dikumandangkan AS dan sekutunya adalah modern (neo-barbarisme), bermodalkan teknologi persenjataan modern.” 10. Dalam karyanya yang banyak diperbincangkan, The End of History and the Last Man (New York: The Five Press, 1992). 11. Menurut Susetyo, “Demokrasi dunia telah mati akibat perilaku manusia jahat yang berhati iblis. Demokrasi telah dikhianati oleh kekuasaan yang hegemonik. Demokrasi hanya dijadikan tameng untuk merebut kekuasaan dari sesama. Ia menjadi lipstik negaranegara adikuasa untuk mencari dukungan dari negara-negara lain. Penegakan demokrasi di dunia akhirnya binasa di tangan mereka yang selalu haus kekuasaan.” Lihat, Susetyo, “Neo-Barbarisme …” 38 Demokrasi & HAM Vol. 3, No. 2, Mei-September 2003 mengembangkan politik teror dan otoriterianisme. Tudingan yang hampir sama kemudian diarahkan Bush terhadap Saddam Hussein. Bagi Bush, penguasa Irak itu layak disingkirkan, karena “mengembangkan senjata pemusnah massal, menjalankan kebijakan represif terhadap rakyatnya, dan menjalin persekutuan dengan kaum teroris internasional.” Oleh karenanya, agresi terhadap Irak ini diperlukan guna “membebaskan rakyat Irak” dan “menciptakan perdamaian dunia.” Bush jelas menyembunyikan niat jahat yang sebenarnya, yaitu menguasai sumber-sumber minyak milik Irak, baik untuk kepentingan AS sendiri12 maupun untuk kepentingan Israel.13 Berbagai dalih yang dipakainya untuk menyerang Irak dengan mudah dapat dipatahkan. Oleh sebab itu, Irak jelas bukan target akhir dan satu-satunya dari Bush dan para anteknya. Setelah Irak, target berikutnya adalah Iran, Suriah, Libya dan Arab Saudi. Keberhasilan “proyek” Irak akan mendorong Bush— yang dikendalikan kaum Zionis internasional—untuk menjalankan “proyek” berikutnya. Dengan demikian, sangat sulit mempercayai begitu saja argumen-argumen—tentang kepemilikan senjata pemusnah massal Irak, keterkaitan Saddam dengan jaringan “terorisme” internasional, dan sikap represif rezim Saddam— yang dipakai Bush untuk melancarkan agresinya di Irak. Jelas ada perhitungan-perhitungan ekonomi dan bisnis yang mendasari agresi AS ke Irak. Pertama, Irak adalah sebuah negara yang memiliki cadangan minyak kedua terbesar di dunia setelah Arab Saudi. Oleh Centre for Global Energy Studies (CGES) London, Irak diperkirakan memiliki 112 milyar barrel cadangan minyak. Bahkan cadangan minyak Irak diperkirakan lebih tinggi dari angka itu, karena sumber minyak di kawasan Gurun Pasir Barat yang belum dieksploitasi, misalnya, kemungkinan masih bisa menghasilkan sumber minyak tambahan. Dengan memiliki cadangan minyak 112 milyar barrel, Irak merupakan pemilik 11 persen cadangan minyak dunia yang belum sepenuhnya terjamah. Irak memiliki sekitar 2.000 ladang minyak yang menghasilkan sekitar 2,5 juta barrel minyak/ hari dari 15 deposit utama minyak di sebelah utara, selatan, dan timur 12. Menurut Susetyo, “Semua orang tahu, AS tak mampu meredam nafsu menguasai sumber minyak. Demi minyak, Bush menipu dunia dengan menggunakan terminologi terorisme.” Ibid. 13. Setelah agresi AS ke Irak, negeri Yahudi ini sibuk merancang pembangunan pipa minyak dari Irak ke Israel. Riza Sihbudi, Pasca Agresi Amerika ke Irak 39 Irak. Kapasitas sebenarnya ladang-ladang minyak itu diperkirakan dapat mencapai 2,8 juta barrel/hari. Irak juga mempunyai 12 pabrik penyulingan minyak dengan total kapasitas 677.000 barrel/hari, terbesar ada di daerah selatan dan utara. Masing-masing kilang itu memiliki kapasitas 170.000 dan 150.000 barrel/ hari. Sebelum Perang Teluk 1991, Irak mengekspor minyak melalui empat pipa ke Turki, Suriah, Arab Saudi dan dua pelabuhan di Teluk Parsi antara lain di Min-Al-Bakr yang dapat melayani supertankers dan mengapalkan hingga 1,3 juta barrel/hari. Sumber daya minyak Irak diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan impor minyak AS selama hampir satu abad. Kesimpulannya, posisi Timur Tengah (termasuk Irak), masih cukup signifikan dalam pasokan minyak dunia. Kedua, minyak dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi dunia jika harganya tidak stabil, terutama jika harga minyak naik secara tajam. Hal itu menyebabkan nilai impor minyak meningkat, biaya produksi meningkat, yang akhirnya akan menurunkan produktivitas. Produktivitas ekonomi yang anjlok, akan memerosotkan perekonomian, dan menghambat pertumbuhan kesempatan kerja. Pertumbuhan ekonomi tentu penting bagi AS. Irak memiliki potensi memainkan harga minyak dunia karena persediaannya yang melimpah. Bila harga minyak tibatiba merosot US$10 saja, AS diperkirakan akan kehilangan pemasukan pajak sebesar US$100 milyar.14 Oleh karena itu, AS merasa khawatir terhadap kestabilan harga dan pasokan minyak dunia. Misalnya, jika rezim Saddam Hussein mendadak menghancurkan fasilitas minyak di Irak, dan kemudian Kuwait, Iran dan Arab Saudi. Pada Perang Teluk 1991, Irak menghancurkan infrastruktur perminyakan Kuwait. Kekhawatiran lain adalah, adanya potensi pengurangan produksi minyak di Teluk. Itu pernah terjadi melalui aksi embargo terhadap AS dan negara-negara Barat lainnya yang mendukung Israel, ketika terjadi Perang Arab-Israel 1973. AS sangat khawatir, jika kontrol produksi minyak jatuh ke tangan pihak yang anti-Barat, karena ketergantungan negara-negara industri Barat, khususnya AS, pada minyak impor. Oleh sebab itu, penggusuran Saddam di Irak dianggap akan mampu menghentikan permasalahan minyak dunia dengan peningkatan pasokan. Selama ini produksi minyak Irak telah terganggu karena terbatasnya investasi dan faktor politik di 14. Gatra (29 Maret 2003), hlm. 40. Demokrasi & HAM Vol. 3, No. 2, Mei-September 2003 40 negeri ini. Jika ada perubahan rezim di Irak, diharapkan akan ada tambahan pasokan minyak dunia sebanyak 3-5 juta barrel/hari. Ketika ditanya apa alasan AS untuk melancarkan Perang Teluk pada 1991, James Baker saat menjabat Menteri Luar Negeri AS saat itu menjawab bahwa alasannya adalah pekerjaan (jobs). Menurut Baker, penciptaan kesempatan kerja atau lapangan pekerjaan yang ada akan anjlok atau hilang, jika Saddam sepenuhnya mampu mengontrol arus suplai minyak dari Teluk Parsi, atau Saddam bertindak sesuai keinginannya untuk mempengaruhi harga minyak. “Apalagi kalau Saddam berhasil mengontrol minyak Irak dan Kuwait,” kata Baker.15 Ketiga, pada 17 September 2002, Gedung Putih, dengan titipan pesan dari Bush, mengeluarkan dokumen 30 halaman berjudul The National Security Strategy of The United States. Gambaran umum dari dokumen itu adalah, tentang strategi kebijakan nasional AS didasarkan pada keunikan internasionalisasi AS yang merefleksikan kesatuan nilainilai dan kepentingan nasional mereka. Tujuan dari strategi itu adalah membentuk dunia yang—tentu saja menurut persepsi AS—tidak saja “lebih aman,” tetapi juga “lebih baik.” Tujuannya adalah, “kebebasan” ekonomi dan politik, hubungan “serasi” dengan negara-negara lain, dan “penghargaan” pada nilai-nilai kemanusiaan. Untuk mencapai tujuan itu, AS akan meningkatkan aspirasi soal nilai-nilai kemanusiaan; memperkuat aliansi untuk membasmi “terorisme” dan bekerja untuk menghindari serangan pada AS dan sekutunya; bekerja dengan pihak lain untuk “menghindari” konflik regional; mencegah ancaman musuh terhadap AS dan sekutunya dengan senjata pemusnah massal; menciptakan era baru untuk pertumbuhan ekonomi global lewat pasar bebas dan perdagangan bebas; meningkatkan siklus pembangunan dengan membuka komunitas dan membangun sarana demokrasi; menciptakan agenda untuk aksi kerja sama dengan pusat-pusat kekuatan global; serta mentransformasikan lembaga keamanan nasional AS untuk menghadapi tantangan dan kesempatan abad 21.16 Namun, dalam prakteknya penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan diabaikan oleh AS demi perhitungan ekonomi dan bisnis, sebagaimana terlihat dari agresi ke Irak. 15. Simon Saragih, “Alasan Perang dari Perspektif Ekonomi”, Kompas (23 Maret 2003). 16. Ibid. Riza Sihbudi, Pasca Agresi Amerika ke Irak 41 Sejak 1998 ChevronTexas (salah satu perusahaan minyak terbesar di AS) sudah mengincar minyak Irak. Dan, sejak 2002, AS kekurangan pasokan minyak 1,5 juta barel/hari akibat krisis politik di Nigeria dan Venezuela. Sejauh ini, perusahaan-perusahaan AS benar-benar vakum dari bisnis minyak di Irak. Produksi minyak di Irak termasuk terendah di dunia. Namun, hal itu juga sekaligus membuatnya sangat menarik bagi investor asing. Menurut US Energy Information Administration, hanya 15 dari 73 ladang minyak yang telah dikembangkan sebagai akibat Perang Teluk 1991 dan sanksi PBB. Pada awal April 2003, ada pertemuan antara para eksekutif perusahaan minyak AS dengan Dick Cheney dan para pejabat Deplu AS. Topik yang dibahas: “kepentingan menata industri minyak Irak pasca Saddam.” Saat itu kubu garis keras yang dimotori Cheney dan Rumsfeld menghendaki kontrol penuh AS atas minyak Irak, yang ditolak kubu (Menlu AS) Collin Powell.17 Keempat, konflik internasional selalu melahirkan tragedi kemanusiaan, yaitu situasi di mana setidaknya ribuan warga sipil akan menderita kelaparan atau mati tanpa bantuan internasional. Pada 1999 PBB menemukan kondisi itu di 23 negara. Akibat situasi itu PBB harus menanggung beban besar, baik beban kemanusiaan maupun biaya material. Sebagai contoh, lebih dari US$4 milyar yang telah dikeluarkan PBB untuk melaksanakan misinya di Kamboja dan Somalia serta US$5 juta/hari di Yugoslavia untuk keperluan peacekeeping operation oleh NATO. Dalam kasus agresi ke Irak, AS diperkirakan telah menganggarkan dana US$ 60-95 milyar. Dana itu selain digunakan untuk operasi militer, juga untuk rehabilitasi fisik dan kemanusiaan Irak pascaperang.18 Kelima, setiap berakhirnya sebuah peperangan, pasti disusul dengan tahap rekonstruksi atau pembangunan kembali infrastruktur yang hancur. Pada 1991, ketika Kuwait dibebaskan pasukan Sekutu yang dipimpin AS dari belenggu aneksasi Irak, negara Arab kaya tersebut harus mengeluarkan dana rekonstruksi sampai US$200 milyar. Proyek sebanyak itu jatuh ke kontraktor-kontraktor AS, yang kemudian membaginya kepada negara-negara lain sekutu “proyek” perang tersebut. Jika kasus Kuwait bisa dijadikan sebagai bahan perbandingan, maka 17. Tempo (13 April 2003), hlm. 145. 18. Tubagus Erif Faturahman, “Menghitung Biaya Perang”, Kompas (26 Maret 2003). 42 Demokrasi & HAM Vol. 3, No. 2, Mei-September 2003 biaya rekonstruksi Irak pasca agresi AS diperkirakan tidak akan jauh dari angka US$200 milyar. Jumlah ini jelas sangat signifikan bagi AS, setidaknya sebanding dengan ongkos yang telah dikeluarkan untuk agresinya ke Irak. Artinya, pendarahan (bleeding) pada anggaran defisit AS dapat dihentikan. Sebelum melancarkan agresi ke Irak, defisit anggaran AS pada 2003 diperkirakan mencapai US$300 milyar yang merupakan rekor terburuk selama ini. Begitu melancarkan agresi, proyeksi defisit diduga melonjak menjadi US$400 milyar. Dengan berakhirnya agresi, bleeding anggaran dapat dihentikan dan keadaan yang lebih buruk bagi perekonomian AS dapat dihindari.19 Keenam, pada 5 April 2003, tokoh-tokoh Irak di pengasingan dan sejumlah pejabat senior AS melakukan pertemuan di London. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan bahwa perusahaan-perusahaan minyak internasional akan diberikan peran utama untuk menghidupkan kembali industri perminyakan Irak di masa pasca-agresi.20 Pemerintah Bush juga mendapatkan persetujuan Kongres AS untuk biaya awal rekonstruksi di Irak sebesar US$2,45 milyar. Anak perusahaan Halliburton (terkait dengan Dick Cheney) bernama Kellogg, Brown & Root (KBR), tanpa tender sudah memenangkan kontrak pemadaman api di ladang-ladang minyak Irak yang terbakar selama invasi. Perusahaan AS lainnya bernama Bechtel Group (terkait dengan pemerintahan Ronald Reagan dan mantan Menlu AS George Shultz serta mantan Menhan AS Caspar Weinberger), Fluor Corp (di perusahaan ini Philip Carroll berperan sebagai Chief Executive Officer sekarang), Parsons Corp, Louis Berger Group, dan Washington Group International. Semua perusahaan—yang pernah menyumbang dana kampanye politik Bush-Cheney sebesar US$3,5 juta—telah memenangkan sebagian kontrak bisnis di Irak. Sementara itu, USAID (Badan AS untuk Pembangunan Internasional) pada tahap awal sudah membagi kontrak utama sebesar US$900 juta hanya kepada perusahaan AS. Perusahaan negara sekutu AS hanya berhak sebagai subkontraktor. Perusahaan Stevedoring Service of America yang berpusat di Seattle, ditawari kontrak US$4,8 juta untuk mengelola pelabuhan Umm Qasr. Beberapa perusahaan AS itu punya kaitan politik dengan rezim Bush, salah satunya perusahaan energi dan konstruksi Halliburton Co., yang penah dipimpin Dick Cheney. Pada 19. A Tony Prasetiantono, “Ekonomi Pasca-Perang Irak”, Kompas (11 April 2003). 20. “Minyak Irak Diperebutkan”, Kompas (9 April 2003). Riza Sihbudi, Pasca Agresi Amerika ke Irak 43 saat bersamaan sekitar 80 perusahaan Inggris sudah menunggu untuk memperoleh kontrak di Irak.21 Penunjukan Jay Garner (Presiden SY Technology, sebuah unit dari L-3 Communication Holding Inc.) sebagai “penguasa sementara” di Irak pasca Saddam juga tak terlepas dari perhitungan bisnis rezim Bush. Pada 1999, misalnya, perusahaan milik Garner memperoleh kontrak proyek Star Wars senilai US$365 juta. Dia— yang sangat dekat dengan The Jewish Institute for National Security Affairs yang mendukung kebijakan garis keras razim Sharon—menjadi konsultan sistem rudal Patriot dan sistem pertahanan rudal Arrow Israel. SY Technology juga mendapat kontrak senilai US$1,5 milyar sebagai penyedia jasa logistik untuk pasukan khusus AS di Irak.22 Di sisi lain, tidak sedikit negara di dunia yang sibuk mendekati AS agar mendapat bagian keuntungan ekonomi pasca-agresi. Lebih jauh lagi, kontrak bisnis di Irak dalam tiga tahun (2003-2006) menyangkut omzet sebesar US$30 milyar. Secara total, diperkirakan Irak membutuhkan US$100 milyar atau bahkan lebih untuk memulihkan ekonomi. Itu bukan hanya untuk membangun industri minyak, tetapi juga sarana-sarana lainnya. Namun dari semua pemberitaan yang ada, perusahaan-perusahaan AS terkesan sangat rakus dan ambisius.23 Bisnis minyak Irak pasca-agresi AS, kemungkinan besar akan dipegang oleh ExxonMobil (AS), BP (Inggris) dan Royal Dutch/Shell, ConocoPhilips (AS), ChevronTexaco (AS). Perusahaan yang bergerak di bidang jasa pendukung pertambangan minyak seperti Halliburton dan Schlumberger (keduanya dari AS) juga akan diuntungkan. Bahkan mantan pimpinan Shell Oil Co Philip J. Carroll, juga sudah dipilih AS untuk menjalankan industri perminyakan Irak pasca-agresi AS. Sebelumnya, berbagai perusahaan AS sudah menangani kontrak-kontrak bisnis untuk mengelola pelabuhan di Umm Qsar. Juga lima perusahaan AS lainnya telah memenangkan kontrak bisnis untuk memadamkan ladang-ladang minyak yang terbakar, serta mendapatkan kontrak untuk pembangunan sarana di Irak. 21. Tempo (13 April 2003), hlm. 143. 22. Ibid, hlm. 144. Garner memang hanya selama sekitar tiga pekan menjadi “penguasa sementara” di Irak pasca-Saddam, karena sejak 5 Mei 2003, posisinya digantikan oleh Lewis Paul Bremer III, seorang diplomat kawakan yang juga dikenal dekat dengan kalangan “neo-konservatif” (seperti Henry Kissinger) dan lobi Yahudi. Lihat juga, Tempo (18 Mei 2003), hlm. 134-135 dan Kompas (12 Mei 2003). 23. “Pada Era Rekonstruksi Irak”, Kompas (13 April 2003). Demokrasi & HAM Vol. 3, No. 2, Mei-September 2003 44 Besarnya peranan yang telah dan akan dimainkan para pelaku bisnis minyak AS di Irak pasca-agresi, mendapat reaksi cukup keras dari sejumlah negara Uni Eropa. Pada 10 April 2003, misalnya, Komisi Eropa telah mengusut kontrak-kontrak bisnis AS di Irak yang baru diumumkan setelah terjadinya agresi. Mereka mengusut, apakah kontrak-kontrak itu sudah sesuai dengan aturan main World Trade Organization (WTO). “Kami sekarang mengevaluasi apakah kontrak-kontrak itu sudah sesuai dengan aturan WTO,” kata Arancha Gonzalez, juru bicara Komisi Perdagangan UE. 24 Alan Larson, Wakil Menlu AS untuk urusan ekonomi, bisnis, pertanian, memberikan jawaban bernada membela perusahaan AS. “Kontrak bisnis itu dilakukan untuk memastikan agar warga Irak bisa dilayani secepat mungkin, bukan untuk menggarap manfaat ekonomi semata pada era rekonstruksi.”25 Namun, Eropa tidak yakin dengan jawaban itu. Karena itu, perusahaan-perusahaan Eropa mengancam. “Kalau ada pihak yang ingin menyingkirkan Lukoil, kami akan menggugatnya melalui pengadilan arbitrase di Geneva, yang akan segera menyita ladang minyak itu,” kata Wakil Presiden Lukoil (Rusia) Leonid Fedun.26 Ada ketakutan dari perusahaan Rusia, Perancis, Jerman, bahwa kontrak-kontrak bisnis yang sudah mereka genggam akan hilang begitu saja. Maka tidak heran, jika trio Prancis-Jerman-Rusia yang paling keras menyuarakan agar wewenang di Irak dikembalikan ke Irak. Pada 8 April 2003, perusahaan minyak utama Rusia Lukoil mengancam akan memblokir untuk jangka watu lama pengembangan ladang minyak raksasa West Qurna di Irak. Tindakan ini akan dilakukan jika ada perusahaan AS atau Inggris yang berambisi merebut peran utamanya dalam proyek itu. 27 Konvensi Geneva memang melarang negara yang menduduki suatu negara untuk melakukan komitmen jangka panjang, khususnya komitmen komersial. Oleh sebab itu, pertarungan memperebutkan lahan bisnis di Irak pasca-agresi AS, diperkirakan akan semakin meningkat tajam di waktu mendatang. 24. Ibid. 25. Ibid. 26. Ibid. 27. Ibid. Riza Sihbudi, Pasca Agresi Amerika ke Irak 45 Berakhirnya Kekuasaan Saddam Seperti yang sudah banyak diperkirakan sebelumnya, runtuhnya rezim Saddam Hussein tak bisa dielakkan. Bagaimanapun, kekuatan militer ASInggris tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan militer Irak. Ini memang sebuah “perang” (lebih tepat disebut agresi atau invasi) yang sangat tidak adil dan tidak berimbang. Betapa tidak, Irak pascaperang Kuwait 1991 secara ekonomi-politik-militer dijatuhi hukuman oleh PBB—atas tekanan AS—berupa embargo dan sanksi di hampir segala sektor kehidupan, kecuali untuk bahan makanan dan obat-obatan. Selain itu, Irak pun dilucuti senjatanya oleh PBB—lagi-lagi atas tekanan AS. Bahwa Saddam itu “monster” (dan bahkan “preman” karena kegemarannya memeras para emir yang kaya di sekitarnya) jelas sulit dibantah. Ia bahkan bukan sekedar “monster” bagi para tetangga Arabnya, melainkan juga bagi rakyatnya sendiri. Mungkin sudah sulit dihitung berapa nyawa yang melayang akibat kekejaman mesin politik Saddam sejak ia berkuasa pada 1979. Namun, mayoritas rakyat Irak— termasuk sekitar 60 persen warga Syiah yang selama ini terpinggirkan— jelas lebih membenci para agresor AS dan Inggris ketimbang Saddam. Oleh sebab itu, harapan AS dan Inggris bahwa para serdadu mereka akan disambut hangat warga Irak menjadi sia-sia belaka. Di samping itu, di mana letak moralitas AS dan Inggris? Pada 1980an AS dan Inggris jelas ikut andil dalam membangun kekuatan militer Irak di bawah Saddam. Entah berapa juta atau bahkan milyar dolar yang sudah dikantongi AS dan Inggris dari rezim Saddam. Yang jelas di bawah Saddam, Irak membelanjakan sekitar 51% dari GDP-nya untuk membangun sektor pertahanan. Kemudian AS dan Inggris memberikan dukungan penuh ketika Saddam “didorong” untuk menyerbu Iran guna mencegah meluasnya revolusi Islamnya Imam Khomeini. Setelah sukses membendung pengaruh Imam Khomeini (yang sangat ditakuti AS dan para sekutunya), justru Saddam sendirilah yang kemudian dihancurkan. Dengan kata lain, Irak terlebih dulu dilemahkan sebelum akhirnya diserang habis-habisan. Ibarat seorang anak manusia yang dirampok hartanya kemudian tak diberi makan berhari-hari lantas dipukuli bertubitubi. Daya tahannya pasti sangat terbatas. Begitu pula halnya dengan Irak di bawah Saddam. Bagi sebagian warga Irak, kejatuhan Saddam memang disambut dengan penuh antusias. Ketika Saddam masih berkusa, di kalangan rakyat Irak ada motto yang sangat terkenal yaitu: “dengan darah dan nyawa, kami rela 46 Demokrasi & HAM Vol. 3, No. 2, Mei-September 2003 berkorban demi Saddam.” Tidak jelas, apakah karena motto inilah maka Saddam Hussein mampu bertahan selama 24 tahun. Juga, tidak jelas apakah “kerelaan” rakyat Irak untuk berkorban demi Saddam itu sematamata karena kecintaan mereka kepada sang pemimpin. Atau, justru karena ketakutan mereka kepada mesin politik Saddam yang sering digambarkan sebagai sebuah “republic of fear” itu. Pasalnya, di negara dengan sistem politik yang amat tertutup seperti Irak, sulit untuk membedakan antara kecintaan dan ketakutan rakyat pada sang pemimpin. Seorang pedagang di Baghdad misalnya—sebagaimana dikutip Sandra Mackey—memberikan ilustrasi yang menarik, “This is radio, but if Saddam says this is refrigerator, it is refrigerator.” 28 Saddam yang pada 28 April 2003 genap berusia 66 tahun sering digambarkan—terutama oleh media AS—sebagai penguasa paling otoriter di kawasan Timur Tengah. Ini tidak mengherankan, karena Saddam bukan hanya tidak mau memberikan ruang gerak bagi perbedaan pendapat (apalagi oposisi) di kalangan warga Irak, tapi ia juga tidak segan-segan untuk “menghabisi” para lawan politiknya dengan caracara yang amat kasar. Belum setahun meraih jabatan presiden (Juli 1979), Saddam sudah mengeksekusi pemimpin Syiah Irak Ayatullah Muhammad Baqer al-Sadr (pada April 1980), yang sejak awal menentang rezim Partai Ba’th. 29 Saddam menganggap warga Syiah—yang jumlahnya mencapai sekitar 60% dari seluruh penduduk Irak vis-à-vis 17% warga Arab Sunni—sebagai ancaman utama. Sikap represif Saddam memang tidak hanya tertuju pada kaum Syiah, melainkan juga terhadap warga Kurdi—sekitar 20% dari seluruh penduduk Irak—dan kalangan Partai Ba’th sendiri, khususnya mereka yang menentang kebijakan sang pemimpin (selain sebagai presiden, Saddam juga memegang jabatan sebagai Ketua Dewan Komando Revolusioner [RCC], Sekjen Komando Regional Partai Sosialis Ba’th Arab, dan Panglima AB). Di antara para tokoh Partai Ba’th dan anggota RCC yang di eksekusi sejak Saddam berkuasa, terdapat nama-nama seperti: Menteri Urusan Kurdi Khaled Abed Osman, Deputi PM ‘Adnan Husain, Menteri Pendidikan Mohammad Mahjoub, Menteri Industri 28. Sandra Mackey, Passion and Politics: The Turbulent World of the Arabs (New York: Penguin Book, 1994). 29. Chibli Mallat, The Middle East into the 21st Century: Studies on the ArabIsraeli Conflict, the Gulf and Political Islam (Ithaca, NY: Ithaca Press, 1997). Riza Sihbudi, Pasca Agresi Amerika ke Irak 47 Mohammad ‘Ayeh, dan Menteri Kesehatan Riyadh Ibrahim.30 Namun, yang membuat dunia ikut terperangah adalah ketika Saddam, pada Februari 1996, tega “menghabisi” dua menantunya yang juga masih dari lingkungan keluarganya sendiri, yaitu Saddam Kamil al-Majid dan Hussein Kamil al-Majid. Dalam perjalanan sejarah Irak modern, Saddam tercatat sebagai pemimpin Irak yang—menurut Mackey—”memperkenalkan cara-cara kekerasan dan teror dalam jaringan keamanan negara guna mempertahankan kekuasaannya.” Ia pun tercatat sebagai pemimpin yang—sebelum terjadinya agresi AS—menjerumuskan bangsa dan negaranya ke dalam dua perang besar: melawan Iran (1980-1988) dan melawan Sekutu (1990-1991). Bahkan sejak Saddam berkuasa, rakyat Irak praktis hanya selama dua tahun menikmanti suasana perdamaian. Ia sangat terobsesi untuk menjadi “pemimpin Dunia Arab.” Karena itu, Saddam—yang dalam biografi resminya diterjemahkan sebagai “pejuang yang tabah”—menyebut perang Irak-Iran sebagai perang antara “bangsa Arab melawan bangsa Parsi,”31 dan ia memang didukung oleh mayoritas negara Arab. Tapi ketika ia menyerbu Kuwait, yang terjadi justru sebaliknya. Mengapa Saddam identik dengan politik kekerasan dan kekerasan politik? Tampaknya ini tidak terlepas dari latar belakang pribadinya yang sejak kecil sudah akrab dengan kehidupan yang serba keras. Pada usia kanak-kanak ia berada di bawah asuhan ayah tirinya, Ibrahim al-Hassan yang digambarkan—oleh Musallam Ali Musallam—sebagai “a crude, brutal and illiterate peasant.”32 Memasuki usia remaja, Saddam mulai terlibat dalam aktivitas politik dengan menjadi anggota Partai Ba’th. Pada usia 22 tahun ia sudah menjadi bagian dari “regu penembak” Ba’th yang melakukan usaha pembunuhan terhadap Jenderal Abdul Karim Qassim, PM Irak waktu itu. Dan, pada usia 31 tahun, sebagai asisten sekjen partai, Saddam menjadi bagian penting dari keberhasilan kaum 30. Samir al-Khalil, Republic of Fear: The Inside Story of Saddam’s Iraq (London, Hutchinson, 1990). 31. Oleh sebab itu, salah satu pasukan elite Irak di bawah Saddam diberi nama “AlQaddisiyyah,” yang diambil dari nama salah satu perang dalam sejarah Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW antara pasukan Arab (Islam) melawan pasukan Persia. 32. Musallam Ali Musallam, The Iraqi Invasion of Kuwait: Saddam Hussein, his State and International Power Politics (London: British Academic Press, 1996). 48 Demokrasi & HAM Vol. 3, No. 2, Mei-September 2003 Ba’this dalam mengambil-alih kekuasaan di Irak (dikenal sebagai “revolusi 1968”).33 Sebelas tahun kemudian (1979), giliran bossnya sendiri, Ahmad Hassan al-Bakr, yang ia depak. Padahal selain menjadi Sekjen Partai Ba’th dan Presiden Irak waktu itu, al-Bakr juga masih tergolong keluarga dekat Saddam. Di bawah kepemimpinan Saddam, Irak memang berhasil menjadi salah satu kekuatan politik-militer yang tangguh di kawasan Timur Tengah, khususnya Teluk Parsi. Dibanding para penguasa Irak sebelumnya, Saddam lebih mampu menciptakan stabilitas politik domestik dan menjadikan negaranya—sebelum terkena sanksi PBB pasca-invasi ke Kuwait—sebagai pengekspor minyak terbesar kedua di kalangan OPEC. Tapi, keberhasilan Saddam membangun kekuatan militer Irak,34 tidak bisa dilepaskan dari peranan negara-negara Barat, termasuk AS. Tanpa dukungan dan bantuan Barat, maka hampir mustahil Irak di bawah Saddam dapat mengembangkan berbagai jenis senjata pemusnah massal (sebagaimana yang selalu dituduhkan AS). Kebijakan AS terhadap Irak waktu itu dilandasi oleh kekhawatiran mereka terhadap kemungkinan meluasnya pengaruh revolusi Islam Irannya Khomeini ke negara-negara sekitarnya. Ternyata, apa yang dilakukan AS terhadap Irak waktu itu lebih mirip “memelihara seekor anak singa.” Setelah besar, sang singa justru bersiap menerkam majikannya. Oleh karena itu, sejak awal dekade 1990an, dengan susah payah AS (dan Inggris) berupaya keras untuk menggulingkan Saddam. Setelah berbagai aksi militer—baik yang legal maupun ilegal ditinjau dari sudut hukum internasional—terhadap Irak tidak mampu menjatuhkan kekuasaan Saddam, AS juga mendorong terjadinya “perlawanan dari dalam.” Waktu itu, AS menyusun tiga alternatif skenario: membujuk pasukan elite Garda Republik untuk mengucilkan Saddam; atau, melemahkan Garda Republik; atau, melemahkan militer Irak seraya mempersenjatai kelompok oposisi, khususnya yang tergabung dalam Kongres Nasional Irak (INC). Tidak terlalu sulit bagi AS untuk menggulingkan Saddam dan kemudian membentuk sebuah pemerintahan boneka, sebagaimana yang 33. Beberapa sumber media Barat menyebutkan, AS ikut mambantu kudeta yang dilancarkan kaum Ba’this pada 1968. 34. Di bawah Saddam, Irak diperkirakan membelanjakan sekitar 51% GDP negaranya untuk membangun sektor pertahanan. Riza Sihbudi, Pasca Agresi Amerika ke Irak 49 telah mereka lakukan di Afghanistan (ketika menggulingkan Taliban). Namun, “model Afghanistan” kendati terbukti berhasil meruntuhkan rezim lama, dalam prakteknya belum sepenuhnya berhasil menciptakan stabilitas politik di negara ini. Di samping itu, Irak jelas bukan Afghanistan. Sekalipun Saddam “ditakuti” dan tidak disukai oleh kebanyakan pemimpin di Timur Tengah, namun mereka umumnya tidak menyetujui jika Washington terlalu jauh melibatkan diri dalam pergulatan politik domestik di Irak. Ini terbukti dari kurangnya dukungan dari sejumlah pemimpin Timur Tengah terhadap AS. Turki, misalnya, sebagai anggota NATO, hampir selalu mendukung setiap aksi militer AS-Inggris terhadap Irak, namun Ankara justru khawatir terhadap kemungkinan munculnya “negara Kurdi” di Irak utara. Maklum, sebagaimana Irak, Turki pun memiliki sekitar 20% warga Kurdi. AS boleh saja “berkampanye” bahwa agresinya dimaksudkan untuk menegakkan sebuah tatanan politik yang demokratis di Irak. Faktanya, hampir semua rezim yang pro-AS di Timur Tengah justru tidak menjalankan prinsip-prinsip politik yang demokratis. Mengapa AS tidak “mendemokratiskan” para sekutunya terlebih dulu sebelum melakukannya terhadap Irak? Hal ini sangat kecil kemungkinan dilakukan Bush, mengingat mayoritas kekuatan oposisi di negara-negara Arab sekutu Washington justru didominasi kelompok-kelompok yang anti-AS. Oleh karena itu, sangat diragukan jika AS benar-benar akan mendorong proses demokratisasi di Timur Tengah, termasuk Irak. Asumsi yang paling sederhana, jika proses demokratisasi berjalan di Irak, maka hampir dipastikan kekuasaan akan jatuh ke tangan kaum Syiah (sebagai kekuatan mayoritas). Apakah AS akan membiarkan munculnya rezim Syiah di Irak? Tampaknya tidak. Betapa pun, membiarkan kaum Syiah mengendalikan kekuasaan di Irak, akan sama artinya dengan menciptakan “Iran baru” di kawasan ini.35 Padahal, sejak kemenangan kaum Syiah dalam revolusi 1979, Iran selalu dianggap sebagai “musuh” oleh AS. Belum lagi jika melihat sikap pasif AS terhadap kasus-kasus pembatalan pemilu di Aljazair (1992) serta pembekuan Partai Refah oleh rezim militer di Turki (1997). 35. Apalagi, tidak lama setelah kembali dari pengasingannya di Iran, Ayatullah Mohammed Baqir al-Hakim, ulama tinggi Syiah, meminta AS segera meninggalkan Irak dan membiarkan rakyat Irak menentukan pemerintahannya sendiri. Kompas (13 Mei 2003). 50 Demokrasi & HAM Vol. 3, No. 2, Mei-September 2003 Dampak Agresi Amerika Berakhirnya riwayat kekuasaan Saddam jelas akan membawa dampak sangat besar, baik dalam arti positif maupun negatif, bagi kawasan Timur Tengah. Positif jika, pertama, AS dan Inggris (juga PBB) mampu mendorong terbentuknya rezim baru di Irak yang demokratis. Ini sesuai dengan komitmen awal AS dan Inggris yang selalu mendengungkan slogan “akan membebaskan” rakyat Irak dari cengkeraman sebuah rezim yang otoriter dan menindas, serta akan mengembalikan hak-hak rakyat Irak atas potensi kekayaan minyak negara mereka. Kedua, AS secepatnya memenuhi janjinya untuk mewujudkan terbentuknya sebuah negara Palestina merdeka. Sumber dari segala sumber konflik akut di kawasan Timur Tengah adalah masalah Palestina. Dalam hal ini tentu yang dimaksudkan adalah hak-hak sah bangsa Palestina untuk mendirikan dan memiliki sebuah negara yang merdeka dan berdaulat serta diakui dan dilindungi oleh lembaga-lembaga internasional. Dukungan AS bagi pembentukan negara Palestina akan dapat meminimalisir sentimen anti-AS yang (sejak agresi ke Irak) berkobar di sanubari mayoritas rakyat Arab, yang dengan sendirinya juga akan mengurangi berkembang-biaknya aksi-aksi “terorisme”. Ketiga, setelah terbentuknya pemerintahan yang demokratis di Irak dan berdirinya negara Palestina merdeka, AS juga mendorong terjadinya proses demokratisasi di negara-negara Arab lainnya yang menjadi sekutu utamanya. Ini diharapkan akan dapat mencegah munculnya “monstermonster” baru di Dunia Arab setelah berakhirnya era Saddam Hussein. Ini sekaligus juga dapat mengantarkan Timur Tengah memasuki era baru, yaitu sebagai zona perdamaian dan demokrasi. Sebaliknya, jika ketiga hal itu tidak dilakukan AS setelah berakhirnya kekuasaan Saddam di Irak, maka yang akan terjadi justru ketidakstabilan politik yang makin meningkat di kawasan ini. Apalagi jika AS hanya mementingkan ambisinya untuk menguasai minyak Irak dan negaranegara Timur Tengah lainnya serta sekedar mengeliminir ancaman militer terhadap Israel. Dengan kata lain dampak yang ditimbulkannya justru akan menjadi sangat negatif. Invasi ke Irak ada kemungkinan besar akan diikuti dengan invasi AS ke Iran, dengan alasan yang sama: menghancurkan senjata-senjata pemusnah massal. Bahkan Suriah, Libya dan Arab Saudi bisa jadi akan menjadi target berikutnya, karena tujuan utama AS adalah menguasai Riza Sihbudi, Pasca Agresi Amerika ke Irak 51 80 persen cadangan minyak dunia serta melindungi kepentingan Israel. Indikasinya sudah terlihat jelas di mana setelah berhasil menduduki Irak, AS mulai mengusik program nuklir Iran 36 serta menuding Suriah “menyembunyikan” para mantan petinggi rezim Saddam Hussein.37 Sementara itu masalah Palestina ada kemungkinan besar akan dilupakan begitu saja,38 karena George W. Bush membutuhkan dukungan kalangan lobi Yahudi AS untuk dapat terpilih kembali dalam pemilihan presiden 2004. Jika ini yang terjadi, maka hampir bisa dipastikan eskalasi kekerasan akan lebih mendominasi panggung politik Timur Tengah pasca-agresi AS ke Irak. Bahwa Irak di bawah Saddam memiliki berbagai jenis senjata pemusnah massal, bisa jadi benar, kendati AS tidak juga berhasil membuktikan kepemilikan senjata pemusnah massal Irak setelah 36. Lihat juga, “Iran confronted on nuclear plans”, International Herald Tribune (May 9, 2003). 37. Dalam wawancara dengan televisi Israel, 12 Mei 2003, setelah berbicara dengan Ariel Sharon, Colin Powell kembali memperingatkan, “jika ingin menjalin hubungan lebih baik dengan AS, Suriah harus tidak mencoba merusak Irak pasca-invasi dan menghentikan upaya melindungi kelompok radikal Palestina.” Kompas (13 Mei 2003). 38. AS memang sudah melontarkan gagasan soal “Peta Perdamaian” (road map) Timur Tengah yang berpedoman pada pidato Bush (24 Juni 2002) tentang solusi konflik Israel-Palestina, dan terdiri dari tiga tahap yaitu: Tahap I (Oktober 2002 - Mei 2003): dihentikannya serangan Palestina, kembalinya koordinasi keamanan Israel-Palestina, pelaksanaan reformasi Palestina, penarikan pasukan Israel dari wilayah A di Tepi Barat, mencabut boikot atas kota-kota di Palestina, dan pembekuan pembangunan permukiman Yahudi. Tahap I (Juni 2003 - Desember 2003): proses lanjutan pelaksanaan reformasi Palestina dan penarikan pasukan Israel ke posisi sebelum meletusnya intifadah Al Aqsa (28 September 2000) serta kembalinya Duta Besar Mesir dan Jordania untuk Israel ke Tel Aviv. Pada tahap ini akan digelar konferensi damai Timur Tengah pertama dan membahas tentang berdirinya negara Palestina dengan perbatasan sementara. Tahap III (2004-2005): menggelar konferensi damai Timur Tengah kedua dan mendeklarasikan berdirinya negara Palestina dengan perbatasan sementara. Konferensi damai tersebut juga membahas jalur Suriah-Israel dan Lebanon-Israel. Pascadeklarasi negara Palestina sementara akan langsung dibuka dengan perundingan membahas isu-isu krusial seperti status Kota Yerusalem, permukiman Yahudi, pengungsi Palestina, dan perbatasan akhir negara Palestina-Israel yang diproyeksikan berakhir pada 2005. Namun banyak kalangan yang pesimis, mengingat selama ini AS terbukti tidak mampu menekan kelompok garis keras di Israel. Rezim Sharon menunjukkan keengganannya untuk menerima “Peta Perdamaian” bahkan ketika Menlu AS Colin Powell mengadakan lawatan ke Israel, pada 12 Mei 2003. Lihat, Kompas (11 dan 13 Mei 2003); dan Tempo (18 Mei 2003), hlm. 130-131. 52 Demokrasi & HAM Vol. 3, No. 2, Mei-September 2003 berakhirnya kekuasaan Saddam.39 Tapi di kawasan Timur Tengah, Irak jelas bukan satu-satunya. Israel pun sudah lama diketahui memiliki dan mengembangkan berbagai jenis senjata pemusnah massal (termasuk nuklir). Bahkan dibanding Irak di bawah Saddam, Israel di bawah PM Ariel Sharon, menjadi satu-satunya negara di kawasan Timur Tengah yang dengan jelas selalu menjauhi perdamaian. Di luar kawasan Timur Tengah, Korea Utara pun secara terbuka juga sudah mengungkapkan program senjata nuklirnya. Namun, terhadap Irak dan Korea Utara, PBB (yang dikendalikan AS) berlaku diskriminatif. Saddam bisa jadi telah melakukan pembantaian terhadap ribuan warga sipil (khususnya dari etnis Kurdi dan kaum Syiah di Irak selatan), namun hal yang sama juga dilakukan Sharon terhadap warga sipil Palestina. Ironisnya, AS dan PBB begitu mudah menjatuhkan resolusi yang tegas dan keras terhadap Irak, namun hal yang sama tidak pernah mereka lakukan terhadap Israel. Memang, kuatnya dominasi lobi Yahudi terhadap politik AS, khususnya di bawah Bush, tidak bisa dipungkiri. Namun, sebagai badan internasional yang bertugas mengayomi warga dunia, PBB seharusnya dapat berlaku adil terhadap semua negara anggotanya. Yang terjadi kini, PBB justru makin terjebak dalam politik standar ganda AS di Timur Tengah. Tuduhan Bush soal adanya persekutuan Saddam dengan kelompok “terorisme” internasional, khususnya Al-Qaeda dan Osama Bin Laden juga sulit diterima akal sehat dan cenderung mengada-ada. Hal ini sebenarnya tidak lebih dari sekedar akal-akalan Bush guna mendapatkan simpati masyarakat internasional bagi agresinya terhadap Irak. Banyaknya keluarga korban Peristiwa 11 September 2001 yang mengikuti aksi unjukrasa antiperang di AS, menunjukkan bahwa upaya Bush untuk mengaitkan Saddam dengan Osama kurang mendapat respons positif dari rakyat AS sendiri. Dengan menyebarkan tuduhan adanya persekutuan Saddam-Osama, Bush hendak mendeklarasikan bahwa agresinya terhadap Irak adalah sama dengan perang melawan “terorisme” internasional, oleh karenanya warga dunia harus mendukungnya. Padahal sebagai seorang fundamentalis garis keras, kecil kemungkinan Osama bersekutu dengan Saddam yang sosialis dan sekuler. 39. Bagaimanapun AS adalah salah satu pemasok utama peralatan militer Irak, termasuk berbagai jenis senjata kimia dan biologi yang dipakai Irak dalam perang melawan Iran (1980-1988). Namun, kemungkinan besar Irak sudah menghancurkan senjata-senjata pemusnah massalnya seperti yang dikehendaki DK PBB. Riza Sihbudi, Pasca Agresi Amerika ke Irak 53 Seperti sudah disinggung di atas, agresi ke Irak memang menjadi kebutuhan Bush guna menaikkan popularitasnya di dalam negeri (kendati sebenarnya banyak rakyat AS yang menentangnya), atau guna menutupi berbagai kegagalannya dalam menangani berbagai persoalan (khususnya ekonomi) domestik, atau untuk mengalihkan perhatian dari kegagalannya memburu Osama dan Mullah Umar di Afghanistan, atau untuk menciptakan sebuah rezim boneka di Baghdad guna lebih menjamin suplai minyak Timur Tengah (serta memajukan bisnis minyak keluarga Bush?), atau pun sekedar untuk melampiaskan dendam ayahnya (Bush senior) yang gagal menggulingkan Saddam Hussein. Namun, seharusnya Bush dan para penasehatnya menyadari, agresi AS ke Irak justru kontra-produktif terhadap doktrin perang melawan “terorisme” internasional yang dikembangkan Washington pasca peristiwa 11 September 2001. Karena Bush benar-benar mewujudkan rencananya dalam menyerang Irak, maka sebenarnya tidak ada bedanya ia dengan kaum “teroris” yang tengah diperanginya. Yang paling banyak menjadi korban dari serangan militer AS adalah para warga sipil Irak (yang sudah menderita akibat 12 tahun embargo PBB yang disponsori AS), bukan Saddam Hussein atau penguasa Irak lainnya. Padahal kaum “teroris” juga selalu mengorbankan warga sipil demi tujuan-tujuan politiknya. Implikasi serius lainnya dari agresi AS ke Irak adalah makin menebalnya sentimen anti-AS di Dunia Arab khususnya serta di Dunia Islam pada umumnya. Selama ini masyarakat Arab dan Islam menyoroti dengan kritis kebijakan AS yang justru selalu mendukung penuh pelanggaran hak-hak asasi manusia yang setiap hari dilakukan penguasa dan militer Israel terhadap warga sipil Palestina. Agresi dan pendudukan AS terhadap Irak justru semakin memperkuat asumsi bahwa AS sebenarnya tidak sedang memerangi “terorisme”, melainkan memerangi bangsa dan rakyat Arab yang mayoritas muslim. Kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan. Dan, selanjutnya akan terciptalah lingkaran kekerasan yang makin sulit dikendalikan. Oleh sebab itu, agresi AS ke Irak pada hakekatnya justru membuka peluang besar bagi peningkatan gerakan-gerakan radikal pro-kekerasan atau “terorisme” yang dilakukan kaum tertindas atau mereka yang termarjinalisasikan. Bila AS berhasil menciptakan sebuah pemerintahan boneka dan melanggengkan pendudukannya di Irak, maka kemelut berkepanjangan di seluruh Timur Tengah menjadi sulit dihindarkan. 54 Demokrasi & HAM Vol. 3, No. 2, Mei-September 2003 Proses radikalisasi akan terjadi. Sikap anti-AS pun akan makin tumbuh subur. Bukan tidak mungkin, pembunuhan terhadap warga AS dan sekutunya di Timur Tengah akan menjadi peristiwa yang makin mewarnai politik di kawasan ini, sebagaimana yang terjadi di kota Riyadh, Arab Saudi, 12 Mei 2003, yang menewaskan sedikitnya 10 warga AS dalam serangan “bom bunuh diri” yang dilakukan warga Saudi. Aksi serupa juga terjadi di Casablanca (Maroko), 16 Mei 2003—yang menewaskan 40 orang—dengan target utama Pusat Komunitas Yahudi, rumah makan Spanyol dan Konsulat Belgia. Sebelumnya seorang warga AS dibunuh di Kuwait. Dengan kata lain, gambaran suram akan menyelimuti kawasan Timur Tengah pascaagresi AS ke Irak. Jika demikian halnya, maka sebenarnya siapakah yang pada hakekatnya bertanggung-jawab dan patut disalahkan dalam hal berkembang-biaknya fenomena terorisme internasional? Saddam Hussein, Osama Bin Laden, atau justru George W. Bush sendiri? ANALISIS Reformasi PBB, Masalah Keamanan dan Perdamaian Internasional: Isu dan Pemecahannya Philips J Vermonte1 PENDAHULUAN Wacana mengenai usaha mereformasi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) senantiasa muncul dan menurut sebagian pihak reformasi ini telah menjadi keharusan yang mendesak. Apalagi sejak Perang Dingin usai yang kemudian menjadikan Amerika Serikat (AS) sebagai satu-satunya super power yang tersisa. Dilihat secara sepintas, berakhirnya Perang Dingin telah meniadakan struktur politik dan keamanan internasional yang bipolar serta membawa struktur baru yang unipolar. Pandangan mengenai struktur unipolar ini sangat riskan karena ia akan memberikan justifikasi pada aksi-aksi unilateralis dari negara super power yang tersisa yang pada akhirnya akan menegaskan eksistensi lembaga multilateral seperti PBB. Walaupun demikian, beragam analisis mengenai persoalan ini menyatakan bahwa struktur politik internasional saat ini sama sekali bukanlah struktur yang unipolar, yaitu struktur yang memprasyaratkan kehadiran sebuah negara super power yang sangat kuat dan mampu mengatasi persoalan serta menjaga keamanan dan perdamaian internasional secara sendirian.2 1. Peneliti Departemen Hubungan Internasional Centre for Strategic and International Studies (CSIS). 2. Lihat misalnya tulisan Samuel Huntington, “The Lonely Superpower”, Foreign Affairs, vol. 78/2 (March/April, 1999), hal. 35-49. 56 Demokrasi & HAM Vol. 3, No. 2, Mei-September 2003 Oleh Karena itu, relevansi PBB justru menemukan kembali momentumnya setelah Perang Dingin usai. Sebab, untuk adanya perubahan konstelasi politik internasional yang signifikan, diperlukan sebuah institusi multilateral yang memiliki legitimasi untuk menjamin keamanan dan perdamaian dunia. Beranjak dari pemahaman ini, PBB memerlukan sebuah penataan ulang agar mampu menyesuaikan diri dan dapat menjalankan tugasnya secara efektif sesuai mandat yang telah diberikan oleh masyarakat internasional. Atas dasar itu pula, wacana mengenai reformasi PBB kembali menguat, apalagi sejak dua aksi militer yang dimotori oleh Amerika Serikat ke Afganistan tahun 2001 dan ke Irak untuk menggulingkan rezim Saddam Hussein pada tahun 2003. Walapun demikian, tulisan ini didasarkan pemahaman bahwa keharusan melakukan reformasi PBB tidak melulu hanya berurusan dengan seruan untuk mengurangi kecenderungan unilateral dari negara-negara besar (utamanya AS). Akan tetapi, ia juga terkait dengan persoalan yang jauh lebih mendasar yakni usaha untuk menjadikan PBB sebagai sebuah lembaga internasional yang mampu beradaptasi dengan lingkup politik internasional yang berubah-ubah. Ringkasnya, kecenderungan unilateral AS hanya merupakan salah satu, dan bukan satu-satunya faktor yang mendorong pentingnya reformasi PBB. Tulisan ini bermaksud memberikan uraian atas wacana mengenai reformasi PBB. Untuk tujuan tersebut, tulisan ini akan dibagi ke dalam tiga bagian. Pada bagian pertama akan dibahas beberapa isu penting yang berkaitan dengan perubahan lansekap politik internasional kontemporer. Pada bagian kedua, akan dipaparkan poin-poin dari reformasi PBB, yang sedang dan telah diselesaikan sejak lama, sebelum peristiwa 911 dan serangan militer ke Irak. Sementara, pada bagian ketiga akan berisi beberapa kesimpulan dan agenda ke depan yang berkaitan dengan persoalan reformasi PBB. Catatan lain yang juga perlu disampaikan adalah bahwa tulisan ini membahas isu reformasi PBB yang terkait dengan kinerja PBB dalam menjaga keamanan dan perdamaian internasional, bukan dalam pengertian reformasi PBB dan keseluruhan badan-badan khusus yang berada di bawah koordinasinya.3 3. Secara paralel juga berkembang wacana mengenai revitalisasi badan-badan khusus PBB seperti WHO, FAO, UNDP, UNHCR, UNICEF dan lain lain. Untuk isu revitalisasi PBB dalam kaitannya dengan badan-badan khusus tersebut, salah satu tulisan yang dapat dijadikan rujukan adalah Koichiro Matsuura, “Revitalizing the U.N. Specialized Agencies”, dalam Japan Review of International Affairs, vol. 13/2 (Summer, 1999), hal. 131-148. Philips J. Vermonte, Reformasi PBB 57 USAINYA PERANG DINGIN Apa Yang (Tidak) Berubah? Selama masa Perang Dingin, peran PBB dalam menjaga keamanan internasional relatif terabaikan. Kedua superpower, AS dan Uni Soviet (US), sering kali mengabaikan PBB antara lain dengan alasan karena kedua negara tersebut sama-sama mengkhawatirkan bahwa PBB akan condong memihak kepada salah satu di antara keduanya. Di sisi PBB, kedua negara tersebut pun tidak pernah diminta mengirim pasukan untuk terlibat dalam peace keeping operations (PKO) pada masa itu. Hal ini sejalan dengan prinsip non-imparsialitas dalam hal pengiriman pasukan penjaga perdamaian sebagaimana yang dikemukakan oleh mantan Sekjen PBB Dag Hammarskjold (yang memulai pengiriman pasukan penjaga perdamaian PBB). Menurut Hammarskjold, PKO adalah “a measure undertaken without prejudice to the rights, claims or positions of the parties concerned”.4 Walaupun demikian, beberapa kasus tetap menunjukkan bahwa PBB, dalam hal ini Dewan Keamanan (DK), dinilai lebih condong kepada kekuatan AS. Sebut saja dalam kaitannya dengan otorisasi yang diberikan oleh DK pada AS untuk mengirimkan pasukan ke Korea pada tahun 1950-an.5 Pada masa Perang Dingin, PBB mengalami dua persoalan utama dalam melaksanakan fungsinya sebagai penjaga perdamaian dan keamanan internasional. Pertama, PBB harus menghadapi politik kedua negara super power yang selalu berusaha menghindari penyelesaian melalui PBB untuk konflik-konflik yang berkaitan dengan negara sekutunya masing-masing. Atau, pada beberapa kasus, konflik yang terjadi bisa mengancam keutuhan PBB karena persaingan kedua negara super power tersebut dalam memperebutkan pengaruh di tubuh lembaga ini. Sebagai contoh adalah dalam misi PBB melalui United Nations Operation in the Congo (ONUC) pada tahun 1960-1964. Negara Kongo, yang baru merdeka dan relatif berada di bawah pengaruh Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet, menghadapi ancaman gerakan separatis dari salah satu provinsinya yang kaya mineral. Gerakan separatis di 4. Lihat Bruce Russet dan James S. Sutterlin, “The U.N. in a New World Order”, Foreign Affairs, vol.70/2 (Spring, 1991), hal. 70. 5. Lihat Jose E. Alvares, “The Once and Future Security Council”, The Washington Quarterly, vol.18/2 (Spring 1995), hal. 6. 58 Demokrasi & HAM Vol. 3, No. 2, Mei-September 2003 provinsi bernama Katanga ini didukung oleh Belgia yang merupakan bekas pemerintah kolonial di Kongo. Selain itu, pemerintah ini juga menghadapi pemberontakan yang dilakukan oleh sebagian anggota angkatan bersenjatanya. Untuk meredam itu semua, pemerintah Kongo meminta bantuan PBB untuk mengirimkan pasukan penjaga perdamaian. Tragedi tersebut terjadi karena ONUC tidak diperkuat dengan mandat untuk menggunakan senjata sehingga akibatnya misi ini terjebak dalam konflik politik di Kongo. Misi ONUC telah menyebabkan lebih dari 200 anggota pasukan perdamaian PBB tewas, bahkan Sekretaris Jenderal PBB Dag Hammarskjold kehilangan nyawanya di Kongo.6 Sejak semula, Uni Soviet telah menolak keterlibatan PBB di Kongo. Setelah peristiwa ini, Uni Soviet bahkan menolak membayar iurannya. Penolakan ini berlangsung selama dua tahun. Melihat kenyataan ini, AS mengancam akan menggunakan artikel 19 dari Piagam PBB yang menyebutkan bahwa ‘any member state whose arrears equals or exceeds the amount of the contribution due from it for the proceeding two years would lose their vote in the General Assembly’. Perselisihan ini hampir mengancam eksistensi PBB, namun kemudian berhasil diselesaikan setelah MU PBB pada akhirnya mencapai kompromi bahwa AS akan menghentikan usahanya untuk mengeluarkan US dan sebagai timbal baliknya US harus menerima keputusan MU PBB untuk membentuk misi perdamaian dalam tubuh PBB yaitu dengan pembentukan Special Committee on Peacekeeping.7 Dari hal di atas, tampak jelas bahwa apa yang terjadi dalam tubuh PBB ketika itu merupakan akibat langsung dari persaingan blok Timur dan Barat dalam memperebutkan pengaruh di negara-negara baru merdeka sejalan dengan proses dekolonisasi. Kedua, dalam konflik yang terjadi antar negara-negara yang relatif tidak berada dalam proxy pengaruh langsung kedua blok super power ini, PBB harus menghadapi isu yang rumit seperti isu kedaulatan dan prinsip-prinsip non-intervensi. Kedua isu di atas memberikan hambatan yang serius bagi PBB untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut. Sehingga, sebagaimana terjadi juga pada masa setelah Perang Dingin, 6. Lihat A.B Fetherston, Towards a Theory of United Nations Peacekeeping (London: Macmillan, 1994), hal.13-15. Periksa juga D. Whitaker, United Nations in Action (London: University College of London, 1995), hal. 31 7. lihat Whitaker, United Nations in Action (1995). Philips J. Vermonte, Reformasi PBB 59 keterlibatan PBB dalam upaya menyelesaikan sebuah konflik selalu menjadi isu kontroversial, karena PBB harus menjaga kenetralan, menjembatani concern mengenai masalah kedaulatan dan isu humanitarian yang tidak mengenal batas geografis dalam waktu yang bersamaan. Penting untuk dipahami bahwa beberapa feature dari politik internasional setelah usainya Perang Dingin tidak mengalami perubahan yang signifikan. Beberapa hal yang konstan, sebagaimana diargumentasikan oleh Robert Jervis (1993) adalah bahwa: politik internasional tetaplah anarkis di mana tidak ada kekuatan yang mengatasi kedaulatan negara-negara di dunia untuk membuat dan menjamin terlaksananya sebuah hukum dan kesepakatan internasional. Di samping itu, beberapa sumber konflik juga tidak mengalami perubahan, seperti pencarian prestise, persaingan ekonomi, nasionalisme yang agresif, standard legitimasi yang berbeda, perselisihan agama dan juga ambisi teritorial.8 Apabila diperhatikan, hal-hal yang tidak mengalami perubahan tersebut justru merupakan inti persoalan dari hubungan antar negara di dunia. Oleh karena itu, bubarnya Uni Soviet justru membuka peluang bagi munculnya konflik-konflik baru, dimana yang sebelumnya ‘diredam’ oleh stabilitas yang diciptakan oleh struktur politik internasional yang bipolar. Kenyataan ini bisa dilihat dari terjadinya peningkatan secara drastis jumlah konflik internal di berbagai negara di dunia. Data PBB menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 1992 hingga 1995, 9 dari 11 operasi keamanan yang dilaksanakan PBB merupakan operasi untuk memulihkan keamanan dan perdamaian dalam konflik yang bersifat intra-states. .... tersebut memperlihatkan adanya peningkatan bila dibandingkan dengan data PBB tahun 1988, di mana hanya satu dari lima konflik yang tercatat pada tahun tersebut yang bersifat intra-states.9 Kecenderungan peningkatan aktifitas PBB dalam isu perdamaian, sebagaimana terekam selama periode 1988 - 1994, bisa dilihat dalam tabel 1. 8. Selanjutnya periksa Robert Jervis, “The Future of World Politics: Will It Resemble The Past?” dalam Lynn-Jones, S.M., Miller, S.E.(eds), America’s Strategy in a Changing World (Cambridge: MIT Press, 1993), hal.10. 9. selanjutnya periksa Boutros Boutros-Ghali, An Agenda for Peace: 2nd edition (New York: UN Publication, 1995). 60 Demokrasi & HAM Vol. 3, No. 2, Mei-September 2003 Tabel 1. Beberapa data aktifitas PBB dalam bidang perdamaian dan keamanan, 1988-1994 Hingga 31 Jan 1988 Resolusi DK yang diadopsi dalam waktu 12 bulan terakhir Perselisihan dan konflik dimana PBB aktif terlibat dalam usaha preventive diplomacy dan peacemaking dalam 12 bulan terakhir Total peacekeeping operation yang dikirim Jumlah personel militer yang dikirim Jumlah polisi yang dikirim Personel sipil internasional yang dikirim Jumlah negara yang ikut menyumbang personel militer dan sipil Budget peacekeeping pertahun (dalam juta dollar) Negara dimana PBB aktif dalam kegiatan elektoral dalam 12 bulan terakhir Sanksi yang dijatuhkan DK Hingga 31 Jan 1992 Hingga 16 Des 1994 15 53 78 11 5 9,570 35 1,516 13 11 11,495 155 2,206 28 17 73,393 2,130 2,260 26 56 76 230.4 1,689.6 1 3,610 6 2 21 7 Sumber: Boutros Boutros-Ghali, An Agenda For Peace (2nd Edition, 1995), hal.8 Joanne Gowa (1989) menyatakan bahwa pertarungan dengan Uni Soviet telah menciptakan perasaan bersatu, sebagaimana konsekuensi dari sumbangan tiap negara dalam koalisi anti – Soviet yang memberi kesempatan pada tiap negara dalam koalisi untuk mengambil manfaat ekonomi dan politik dari koalisi tersebut. Karena setiap negara yang menjadi bagian dari koalisi berusaha menghindari instabilitas politik di dalam negeri masing-masing yang dapat mengguncang koalisi, dan saling membantu menjaga stabilitas politik dengan ....... secara baik masalahmasalah sosial.10 Keadaan yang sama pun terjadi di dalam blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Dengan demikian pada akhirnya terbentuklah sebuah sistem bipolar yang menciptakan stabilitas dalam sistem politik internasional. 10. Joanne Gowa, “Bipolarity, Multipolarity, and Free Trade” sebagaimana dikutip dalam Robert Jervis, The Future of World Politics, hal. 18. Philips J. Vermonte, Reformasi PBB 61 Berakhirnya Perang Dingin juga memunculkan fenomena baru yang berbeda dari dua masalah utama yang dihadapi PBB dalam masa Perang Dingin seperti diuraikan di atas, yakni penyelesaian di luar mekanisme PBB dan persoalan mengenai kedaulatan dan prinsip non-intervensi. Setelah bubarnya Uni Soviet, harapan yang digantungkan kepada PBB untuk menjadi sebuah lembaga internasional yang kredibel meningkat. Beberapa alasan dikemukakan sebagai dasar munculnya harapan tersebut. Diantaranya, Pertama, bahwa secara alamiah AS akan mengkaji ulang kepentingan nasionalnya dan juga keterlibatannya dalam berbagai isu global. Oleh karena itu, dunia akan mengalami situasi di mana tidak ada sebuah global leadership yang efektif untuk mengelola konflik internasional. Akhirnya, PBB akan kembali menjadi tumpuan dan kunci dalam menjalankan fungsi tersebut. Kedua, adalah bahwa PBB menjadi satu-satunya institusi yang paling mungkin mendapat legitimasi untuk menyelesaikan konflik-konflik internal yang berpotensi mengancam keamanan sebuah region dan juga mengancam keamanan internasional yang mengemuka setelah Perang Dingin. Untuk memulihkan perdamaian di wilayah-wilayah konflik, hanya institusi semacam PBB yang menmiliki mandat internasional sehingga dapat terlihat secara intensif, baik secara militer dan non-militer, dalam usaha menyelesaikan konflik-konflik tersebut. Ide dasar pembentukan PBB adalah menjalankan collective security yang berinti pada kesadaran bahwa: “all states would join forces to prevent one of their number from using coercion to gain advantage. Under such system, no government could conquer another or otherwise disturb the peace for fear of retribution from al other government. Any attack would be treated equal as if it were an attack on each of them. The notion of self defense, universally agreed as a right of sovereign states, was expanded to include the international community’s right to prevent war.”11 Namun, pengalaman PBB sejak awal pendiriannya dalam mengimplementasikan ide collective security memperlihatkan beberapa persoalan serius. Thomas G. Weiss dan kawan-kawan12 menggambarkan beberapa persoalan tersebut sebagai berikut: Pertama, negara-negara di 11. Lihat Weiss, T.G., Forsythe, D.P., Coate, R.A., The United Nations and Changing World Politics (Boulder: Westview Press, 1994), hal. 21. 12. Ibid, hal.22-23 62 Demokrasi & HAM Vol. 3, No. 2, Mei-September 2003 dunia secara natural sering menolak bergabung dalam penerapan sebuah sanksi PBB kepada sebuah negara tertentu karena mereka telah menetapkan sendiri siapa kawan dan lawannya masing-masing. Kedua, adanya masalah dalam pendistribusian power. PBB selalu mengalami kesulitan untuk bertindak melawan kepentingan negara-negara yang memiliki nuklir. Selain itu, PBB juga sulit untuk bertindak diluar kepentingan negara-negara yang sangat kuat secara ekonomi. Ketiga, ide collective security relatif mahal biayanya. Misalnya, sanksi ekonomi kepada sebuah negara tidak hanya akan mempengaruhi negara yang terkena sanksi, tapi akan mempengaruhi negara-negara lain yang memiliki hubungan ekonomi dan politik erat dengan negara bersangkutan. Contoh konkritnya adalah ketika PBB menjatuhkan sanksi pada Afrika Selatan yang menjalankan politik apartheid, Bulgaria telah memilih untuk mendukung sanksi tersebut. Namun di lain pihak, Bulgaria tetap melakukan perdagangan senjata dengan rezim tersebut.13 Keempat adalah bahwa ide collective security didasarkan pada asumsi bahwa semua korban (agresi atau konflik) sama pentingnya. Akibatnya, ada anggapan bahwa PBB akan bertindak sama terhadap serangan atas Bosnia, Kuwait, Palestina, Argentina dan lain-lain. Padahal, sejarah menunjukan bahwa tidak pernah semua negara bertindak sama dalam sebuah isu, hal itu disebabkan karena perbedaan kepentingan dan cara pandang masing-masing negara. Dalam kaitan dengan ini, penting untuk diperhatikan pernyataan yang dikeluarkan oleh Presiden AS George W. Bush bahwa AS hanya akan ikut serta dalam misi intervensi di luar wilayahnya selama hal itu bersesuaian dengan kepentingan nasional AS secara langsung. Presiden Bush juga menyatakan bahwa yang ia maksud dengan kepentingan nasional AS adalah “whether our territory is threatened, our people could be harmed [or] whether or not our defense alliances are threatened”.14 Selain itu, AS akan semakin memilih untuk berhati-hati untuk melibatkan diri dalam berbagai konflik internal sebagaimana diingatkan oleh pakar hubungan internasional AS Joseph Nye bahwa 13. Thomas Weiss, The United Nations and Changing World, hal.23. 14. Dikutip oleh Brett D. Schaefer, “The United States and The United Nations: What To Expect In The Future” dalam Heritage Lectures No.730 (The Heritage Foundation: January 2002), hal.3 Philips J. Vermonte, Reformasi PBB 63 ‘a human right policy is not itself a foreign policy; it is an important part of foreign policy’. 15 Keempat persoalan di atas menjadi obyek diskusi dalam wacana mengenai reformasi PBB. Dalam kaitannya dengan permasalahan pertama, kewibawaan PBB untuk menghasilkan sebuah keputusan yang mengikat seluruh anggotanya menjadi persyaratan mutlak. Persoalan kedua mengenai distribusi power yang berkaitan dengan manajemen kekuasaan dalam tubuh PBB sendiri. Ia berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Umum, Dewan Keamanan dan juga dalam hubungannya dengan kepemilikan atas hak veto dari kelima anggota tetap DK PBB. Masalah ketiga dan keempat sangat erat berkaitan satu sama lain, karena perspesi tentang “mahalnya” biaya sanksi yang diterapkan PBB akan ditentukan oleh kepentingan nasional dari masingmasing negara anggota PBB. Kesemuanya ini jelas berkaitan dengan kemampuan PBB sendiri dalam menemukan mekanisme untuk pelaksanaan mandatnya dalam menjaga keamanan dan perdamaian internasional, baik melalui mekanisme sanksi, embargo atau operasi militer dalam payung PBB. Ironisnya, di tengah munculnya harapan untuk menjadikan PBB sebagai sebuah lembaga dunia yang mampu meredam kecender ungan unilateralis dari negara-negara besar, peristiwa seperti serangan AS dan Inggris ke Irak tahun 2003 ini jelas memperlihatkan ketidakberdayaan PBB. Sehingga, wacana untuk mereformasi PBB kembali menguat. Bagian berikut dari tulisan ini akan membahas persoalan reformasi PBB dalam kaitannya dengan keempat hal tersebut. REFORMASI PBB: Apa Yang (Tidak) Mungkin? Masalah Legitimasi Dengan tendensi seperti yang diungkapkan oleh Boutros BoutrosGhali dalam laporannya An Agenda For Peace mengenai peningkatan terjadinya konflik internal di seluruh dunia, tampak jelas bahwa isu utama yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa PBB semakin terdorong 15. Lihat Joseph Nye, “Redefining National Interest”, Foreign Affairs vol.78/4 (July/ August 1999), hal.31. 64 Demokrasi & HAM Vol. 3, No. 2, Mei-September 2003 untuk terlibat dalam berbagai tindakan, baik militer maupun non-militer, dan harus berhadapan dengan prinsip-prinsip kedaulatan dan humanitarian. Walaupun kontroversial, PBB mendapat legitimasi untuk melakukan hal tersebut karena diberi mandat melakukan enforcement sesuai dengan Chapter VII Piagam PBB untuk menghadapi sebuah negara agresor yang mengancam keamanan dan perdamaian internasional. Berbagai pendapat muncul dan menyatakan bahwa kemanusiaan (humanity) adalah nilai yang universal, dan intervensi adalah tindakan yang dapat dibenarkan, sepanjang dilakukan oleh instrumen global seperti PBB. Alasannya adalah bahwa Piagam PBB tidak hanya mengakui kedaulatan negara, akan tetapi juga melindungi hak masyarakat (the rights of the people). Seperti dinyatakan oleh Paul Taylor: “ statehood could be interpreted as being conditional upon respect for such rights: for instance the Preamble held that the organization was ‘to reaffirm faith in fundamental rights’, and article 1 (3) asserted the obligation to ‘achieve international cooperation….in promoting and encouraging respect for human rights and fundamental freedom for all”.16 PBB sendiri telah mendirikan sebuah unit di markas besarnya di New York yang disebut Department of Humanitarian Affairs. Departemen ini dibentuk berdasarkan Resolusi Majelis Umum no.46/182 yang dikeluarkan pada bulan Desember 1991. Resolusi ini merupakan terobosan penting karena ia memberi legitimasi bagi operasi humanitarian PBB. Dalam resolusi tersebut dinyatakan bahwa semua anggota PBB setuju untuk membuka akses bagi setiap misi PBB untuk mengantarkan bantuan kemanusiaan.17 Masalah kemanusiaan juga memberi legitimasi yang kuat bagi PBB untuk melakukan intervensi. Karena di tengah semua konflik, hampir dapat dipastikan warga sipil yang tidak bersenjatalah yang akan menjadi korban utama. Seperti yang dinyatakan Sadako Ogata: “in April 1991, 1.7 million Iraqi Kurds fled to Iran or the Turkish border. UNHCR is assisting over a million Somali refugees in the neighboring countries of Kenya, Yemen, Djibouti and Ethiopia. In the former Yugoslavia, we are 16. lihat Paul Taylor, International Organization in the Modern World: the Regional and the Global Process (London: Pinter, 1993), hal.274. 17. lihat A. Jan, et al., Peacemaking and Peacekeeping for the Next Century: Report of the 25th Vienna Seminar (New York: International Peace Academy, 1995), hal. 41. Philips J. Vermonte, Reformasi PBB 65 protecting and assisting over 1.5 million refuges in Serbia, Croatia and Montenegro as well as almost 3 million displaced and affected population in Bosnia and Herzegovina…in the space of one forthnight, some 600,000 persons fled ethnic killing in Burundi to seek refuge in Rwanda, Tanzania and Zaire”.18 Walaupun demikian, pada banyak kasus, harus diakui pula bahwa PBB tidak selalu siap dalam melakukan operasi peacekeeping ataupun enforcement, karena memang kedua instrumen ini tidak terlembaga di dalam tubuh PBB.19 Proposal untuk pembentukan sebuah “tentara PBB” yang standby dan bertanggung jawab langsung pada Sekretaris Jenderal telah lama muncul. Namun hingga saat ini beragam persoalan teknis yang muncul dalam ide tersebut belum pernah terjawab, semisal aspek legal, pendanaan dan pengelolaan pasukan itu sendiri. Distribusi Power dan Manajemen Kekuasaan Selain Sekretaris Jenderal, Dewan Keamanan dan Majelis Umum juga merupakan institusi yang berperan dalam pengambilan keputusan oleh PBB. Dengan demikian, ketiga organ ini juga masuk dalam agenda reformasi PBB yang luas. Pada prinsipnya, PBB memiliki ‘elemen pemerintahan’ dalam organ-organnya. PBB memiliki Majelis Umum yang berfungsi sebagai organ ‘legislatif ’, Dewan Keamanan sebagai organ ‘eksekutif ’, dan ia juga memiliki International Court of Justice yang berfungsi sebagai organ ‘yudikatif ’.20 Ketiga organ inilah yang membedakan PBB saat ini dari organisasi dunia lain dari waktu ke waktu. Bila sebelumnya international collective security dijalankan oleh institusi berformat konferensi hingga organisasi longgar seperti The Peace of Westphalia (1648), The Peace of Utrecht (1713) dan The Congress of Vienna (1815) serta Liga Bangsa-bangsa (League of Nations) setelah Perang Dunia I, maka PBB saat ini memiliki elemen supranasional yang sebetulnya jauh lebih kuat.21 18. Lihat Sadako Ogata, “The interface between peacekeeping and humanitarian action”, dalam Warner (ed), New Dimension of Peacekeeping (Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1995), hal. 119. 19. lihat John Gerard Rugie, “Wandering in the Void: Charting the U.N.’s New Strategic Role”, Foreign Affairs vol. 72/5 (November/December, 1993), hal. 28. 20. Analogi ini diberikan oleh Nigel D. White dalam tulisannya “Accountability and Democracy Within the U.N: a Legal Perspective”, International Relations vol.XIII/6 (December 1997), hal. 3-4. 21. Ibid 66 Demokrasi & HAM Vol. 3, No. 2, Mei-September 2003 Sebagaimana diketahui, DK yang beranggotakan 15 negara termasuk 5 anggota tetap, jauh lebih powerful daripada MU PBB. Sehingga secara kasat mata, terlihat bahwa DK bisa saja mengadopsi resolusi yang bertentangan dengan aspirasi lebih banyak negara dalam MU. Karena itu persoalan representasi dalam tubuh DK menjadi isu besar dari keseluruhan agenda reformasi PBB. Apabila dilihat dari sejarah pembentukannya, kewenangan yang besar yang diberikan pada DK merupakan akibat dari pengalaman traumatis Perang Dunia II. Saat itu, para pendiri PBB sepakat untuk memberikan mandat utama dan kekuasaan yang besar pada DK untuk memenuhi cita-cita utama pendirian PBB yaitu ‘to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind’.22 Akan tetapi, saat ini persoalan struktur DK semakin mendapat perhatian, tidak hanya karena persoalan pemilikan senjata nuklir oleh beberapa negara, namun juga karena persoalan representasi. Sebenarnya, keanggotaan DK sendiri telah ditingkatkan dari 11 menjadi 15 negara pada tahun 1965. Namun hal ini masih dinilai tidak representatif bagi keanggotaan PBB. Ketika PBB didirikan pada tahun 1945, anggota PBB berjumlah 51 negara, sehingga jumlah 11 negara di DK setara dengan 22 persen dari keseluruhan anggota. Apalagi dengan jumlah anggota lebih dari 185 negara seperti saat ini, persentase itu menjadi jauh lebih kecil hingga hanya 8 persen. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa DK seringkali dinilai tidak demokratis dan sama sekali tidak representatif.23 Untuk mengembalikannya kepada rasio awal, DK harus berjumlah 40 negara namun hal ini relatif sulit dilakukan karena negara anggota PBB akan menunggu giliran terlalu lama untuk menjadi anggota tidak tetap DK tersebut. Olara Otunnu (1993)24 mengajukan dua usul untuk memecahkan masalah ini. Pertama, struktur keanggotaan diusulkan untuk dibagi ke 22. Kalimat ini tertuang dalam baris pertama pembukaan Piagam PBB. 23. Periksa Nigel D. White, Accountability and Democracy Within the United Nations, hal. 5. 24. Lihat Olara A. Otunnu, “Maintaining Broad Legitimacy For United Nations Action” dalam Roper, J et all (eds), Keeping the Peace in the Post-Cold War Era: Strengthening Multilateral Peacekeeping (New York: The Trilateral Commission, 1993), hal. 72-73. Philips J. Vermonte, Reformasi PBB 67 dalam tiga lapisan. Lapis pertama adalah 5 anggota tetap PBB dengan hak veto yang akan sulit untuk dihapuskan. Pada lapis kedua dipilih 5 anggota tetap baru tanpa hak veto. Namun keanggotaannya tidak sepenuhnya tetap, tapi kelima negara ini diberi masa keanggotaan fixed term selama 10 tahun dan bisa dipilih kembali. Beberapa negara yang masuk kualifikasi ini adalah Jepang, Jerman, Brazil mewakili Amerika Latin dan Karibia, India mewakili Asia dan Nigeria mewakili Afrika. Lapis ketiga adalah anggota tidak tetap PBB sebanyak 10 atau 11 anggota dengan mekanisme rotasi seperti yang berlaku saat ini. Usul kedua adalah dengan memberikan hak veto regional. Di mana hak veto baru diberikan kepada negara yang mewakili sebuah kawasan tertentu. Menurut Otunnu, kawasan yang mendesak diberi hak veto regional baru ini adalah Amerika Latin dan Afrika yang memang belum terwakili oleh kelima anggota tetap DK PBB saat ini. Usulan ini muncul untuk mengimbangi ketidakpuasan banyak negara terhadap hak veto yang dimiliki negara-negara anggota tetap DK. Walaupun demikian, isu hak veto sebetulnya tidak menjamin efektifitas kinerja DK. Karena, negara-negara besar bisa saja menghindari pemungutan suara di DK dan mengambil langkah-langkah unilateral seperti serangan atas Irak tahun ini. Selain itu, sebenarnya penggunaan hak veto oleh kelima negara anggota tetap DK itu telah jauh menurun jumlahnya setelah Perang Dingin usai. Selama Perang Dingin, jumlah veto yang terjadi adalah 240, sementara sejak tahun 1990 hingga 1999 hanya terjadi 7 veto.25 Namun demikian, jumlah veto yang kecil tersebut, DK masih tetap bisa di bypass oleh berbagai pihak. Contoh lain di luar serangan terhadap Irak oleh AS dan Inggris adalah ketika NATO memulai aksi militer di Yugoslavia tanpa persetujuan DK PBB. Negara NATO tahu persis bahwa apabila mereka melalui mekanisme PBB, maka Rusia akan mem-veto proposal serangan militer ke negara ex-Yugoslavia yang dipimpin oleh Slobodan Milosevic tersebut.26 25. Periksa Richard Butler, “Bewitched, Bothered, and Bewildered: Repairing the Security Council”, Foreign Affairs vol.78/5 (September/October, 1999), hal.9. 26. ibid. 68 Demokrasi & HAM Vol. 3, No. 2, Mei-September 2003 Prinsip Selektifitas Versus Universalitas Pengalaman NATO di Bosnia dan Kosovo memperlihatkan kerumitan menentukan standard untuk memulai aksi militer PBB dalam menjamin keamanan dan perdamaian internasional. Sebagian besar negara di dunia menyetujui bahwa tindakan Milosevic bertentangan dengan azas perikemanusian dan karena itu membenarkan aksi NATO di negara exYugoslavia itu, walaupun pada awalnya tidak dilakukan dalam kerangka PBB. Di pihak lain, dunia bereaksi keras terhadap aksi unilateral AS dan Inggris di luar kerangka PBB terhadap rezim Saddam Hussein di Irak. Oleh karena itu, tampaknya persoalan utama dari setiap operasi militer PBB adalah menemukan dasar yang kuat untuk menjustifikasinya bahwa negara yang dituju oleh sebuah operasi militer adalah yang secara jelas mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Agaknya, PBB akan sangat sulit memegang teguh prinsip universalitas. Alasannya adalah karena persoalan ini tidak melulu berkaitan dengan imperatif moral humanitarian, akan tetapi ia berkaitan juga dengan kesiapan infrastruktur, dana, dan yang jauh lebih penting dari semuanya adalah kepentingan nasional dari negara-negara anggota PBB. Dalam kasus AS, hal ini telah digambarkan dengan baik oleh Joseph Nye. Nye menyebutkan betapa dorongan moralis rakyat dan pemerintah AS untuk mengirim pasukan ke Somalia untuk membantu penyelesaian konflik di negara tersebut menghilang setelah di layar-layar televisi AS ditampilkan gambar tiga mayat prajurit AS yang diseret di jalan Mogadishu oleh milisi Somalia yang membunuhnya. Akibatnya, AS (dan juga PBB) enggan dan terlambat melakukan intervensi militer dan kemanusiaan di Rwanda pada tahun 1994 karena ketiadaan dukungan dari publik domestik di AS. Padahal, skala kejahatan kemanusiaan di Rwanda jauh lebih besar dari yang terjadi di Somalia beberapa waktu sebelumnya.27 Apabila keterlibatan PBB di Somalia dikaji lebih jauh, tampak bahwa PBB memiliki keterbatasan untuk memberikan bantuan yang komprehensif untuk menyelesaikan konflik, seperti rehabilitasi sosial dan ekonomi bahkan sampai persoalan memulihkan keadilan dan ketertiban melalui pemulihan fungsi kepolisian dan lembaga yudisial.28 27. Periksa Joseph Nye, Redefining the National Interest, hal.32. 28. Lihat misalnya Omar Halim, “Reforming the United Nations: What Has Been Achieved?”, The Indonesian Quarterly vol. XXV/2 (1997), hal. 200. Philips J. Vermonte, Reformasi PBB 69 Di luar kemampuan teknis, masalah ketersediaan dana juga dapat menjelaskan keterbatasan PBB ini. Walaupun banyak kekecewaan yang dilontarkan terhadap AS, harus diakui bahwa AS berperan penting dalam kesiapan PBB melakukan operasi militer untuk menjaga keamanan dan perdamaian internasional. AS telah memberikan sumbangan yang sangat signifikan dalam pendanaan PBB dan juga operasi peacekeeping di berbagai tempat di belahan dunia. Berbagai negara menolak untuk mengurangi jumlah kontribusi dana AS, baru sampai pada tahun 2000 negara-negara anggota PBB setuju mengurangi jumlah yang yang harus dibayar AS, dari 25 persen dari total budget PBB menjadi 22 persen. Bahkan untuk operasi peacekeeping di seluruh dunia, jumlahnya dikurangi dari 31 persen dari total dana yang dibutuhkan menjadi 27 persen.29 Salah satu alternatif untuk mengatasi dikotomi antara prinsip selektifitas dan universalitas adalah dengan cara pemberian kewenangan lebih besar secara legal oleh PBB kepada organisasi-organisasi regional untuk bekerjasama menjalankan fungsi penjaga keamanan dan perdamaian internasional. Dengan cara semacam ini, masalah kurangnya dukungan dari negara-negara besar untuk terlibat dalam operasi militer di wilayah-wilayah yang tidak menempati prioritas dalam kepentingan nasionalnya kemungkinan akan teratasi. Sebetulnya hal ini pun dimungkinkan oleh piagam PBB, sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 52 dan 53 dari Chapter VIII Piagam PBB, yang berbunyi: “Article 52. 1. Nothing in the present Charter precludes the existence of regional arrangements or agenicies for dealing with such matters relating to the maintenance of international peace and security are appropriate for regional action provided that such arrangement or agencies and their activities are consistent with the Purposes and Principles of the United Nations. Article 53. 1 . The Security Council shall, where appropriate, utilize such regional arrangements or agencies for enforcement action under its authority. But no enforcement action shall be taken under regional arrangements or by regional agencies without the authorization of the Security Council.” Salah satu preseden yang bisa dijadikan rujukan oleh PBB adalah adalah tindakan NATO di Bosnia dan Herzegovina beberapa tahun lalu. 29. Periksa Brett D. Schaefer, The United States and the United Nations, fn.1. Demokrasi & HAM Vol. 3, No. 2, Mei-September 2003 70 Pengiriman pasukan penjaga perdamaian oleh Economic Community of West African States (ECOWAS) ke Liberia ketika mengalami konflik internal dapat memberi gambaran mengenai peran organisasi regional. Pendelegasian wewenang juga menjadi alternatif untuk mengurangi beban budget PBB, yang semakin meningkat karena bertambahnya jumlah aktifitas PBB dalam masalah penjagaan keamanan dan perdamaian internasional. Ilustrasi pendanaan PBB dalam peacekeeping operation bisa dilihat dalam tabel berikut: Tabel 2. Biaya Riil Peacekeeping Operation 1989-1995 (dalam milyar dollar) UNPROFOR UNOSOM II UNTAC ONUMOZ UNIKOM UNAMIR UNAVEM I MINURSO 3,132 1,782 1,651 541.7 237.4 236.8 186.3 155.2 ONUSAL UNOMIL UNAMIC UNOSOM I UNAVEM II UNOMIG UNMIH UNMOT 110.8 54.2 37.3 25.2 20.5 14.8 11.3 1.4 Sumber: A. Jan, et al., Peacemaking and Peacekeeping for the Next Century: Report of the 25th Vienna Seminar (New York: International Peace Academy, 1995), hal.93. Singkatan bisa dilihat di bagian appendix tulisan ini. Dalam konteks yang lebih luas, organisasi regional seperti The Organization of American States (OAS) telah melangkah lebih jauh ketika negara-negara anggota OAS dalam pertemuan tahunannya tahun 1991 telah setuju untuk bertindak secara multilateral di kawasannya, apabila terjadi kudeta di salah satu negara anggota yang tentu saja berpotensi menciptakan instabilitas keamanan di kawasan itu. Bahkan dalam Inter-American Democratic Charter yang baru ditandatangani pada bulan September 2001, negara-negara anggota OAS memperkuat komitmennya kembali dengan menyatakan secara terbuka bahwa OAS tidak akan pernah melegitimasi dan mentoleransi pergantian rezim secara inkonstitusional di wilayahnya.30 Komitmen regional semacam ini akan sangat memudahkan PBB dalam usahanya menjaga keamanan dan perdamaian internasional. 30. Lihat Philips J. Vermonte, “Democracy Interrupted: Lessons From Venezuela”, The Jakarta Post 24 Mei 2002. Philips J. Vermonte, Reformasi PBB 71 KESIMPULAN UMUM: BEBERAPA AGENDA KEDEPAN Berdasarkan uraian ini, dapat diringkaskan bahwa reformasi PBB sangat perlu dilakukan karena tantangan yang dihadapi oleh PBB juga semakin besar. Seusai Perang Dingin, PBB kembali menemukan momentum untuk bisa membawa dirinya menjadi sebuah instrumen global yang mendapatkan mandat internasional untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Namun, untuk mampu memenuhi mandat ini, PBB harus menyelesaikan beberapa persoalan mendasar, tidak hanya pada aspek organisasional di tubuh PBB sendiri (dalam hal ini DK), namun juga menemukan formula dan tindakan yang bisa diterima oleh sebanyak mungkin negara melalui perumusan legitimasi yang bisa dibenarkan oleh hukum internasional. Secara organisasional, PBB memerlukan reformasi untuk memperbaiki struktur organisasinya sehingga ia menjadi lebih representatif dan demokratis sesuai dengan perubahan konstelasi politik internasional. Legitimasi yang diberikan dan diamanatkan oleh Piagam PBB harus bisa dioperasionalkan secara teknis. Mengingat “keterbatasan” PBB sebagai sebuah lembaga multilateral yang mensyaratkan mekanisme pengambilan keputusan yang relatif rumit, PBB perlu terus mendorong kerjasama dengan lembaga regional untuk dapat secara bersama-sama menjalankan fungsi penjaga perdamaian dan keamanan internasional sebagaimana diamanatkan oleh Piagam PBB sendiri. Untuk mencapai tujuan ini, PBB perlu mendorong organisasi-organisasi regional untuk mengkaji ulang prinsip nonintervensi dan mendorong penerimaan terhadap prinsip humanitarian, agar pengakuan atas kedaulatan negara juga diikuti dengan pengakuan atas hak individual untuk mendapatkan perlindungan keamanan. Demokrasi & HAM Vol. 3, No. 2, Mei-September 2003 72 Appendix United Nations Peacekeeping Operations Tahun dimulai UNTSO UNMOGIP UNEF I UNOGIL ONUC UNTEA/UNSF UNYOM UNFICYP DOMREP UNIPOM UNEF II UNDOF UNIFIL UNGOMAP UNIIMOG UNTAG UNAVEM I ONUCA ONUSAL MINURSO UNIKOM UNAMIC UNAVEM II UNPROFOR UNOSOM I UNTAC ONUMOZ UNMIH UNOMIG UN Truce Supervision Organization UN Military Observer Group in India and Pakistan UN Emergency Force I UN Observer Group in Lebanon UN Operation in the Congo UN Temporary Executive Authority/ UN Security Force in West New Guinea (West Irian) UN Yemen Observer Mission UN Peacekeeping Force in Cyprus Mission of the Representative of the Secretary-General in the Dominican Republic UN India Pakistan Observer Mission UN Emergency Force II UN Disengagement Observer Force UN Interim Force in Lebanon UN Good Offices Mission in Afghanistan and Pakistan UN Iran-Iraq Military Observer Group UN Transitional Assistance Group UN Angola Verification Mission UN Observer Mission in Central America UN Observer Mission in El Salvador UN Mission for the Referendum in Werstern Sahara UN Iraq-Kuwait Ibserver Mission UN Advance Mission in Cambodia UN Angola Verification Mission UN Protection Force in the Former Yugoslavia UN Operation in Somalia I UN Transitional Agency in Cambodia UN Operation in Mozambique UN Mission in Haiti UN Observer Mission in Georgia 1948 1949 1956 1958 1960 1962 1963 1964 1965 1965 1965 1974 1978 1988 1988 1989 1989 1989 1991 1991 1991 1991 1991 1992 1992 1992 1992 1993 1993 Philips J. Vermonte, Reformasi PBB 73 Tahun dimulai UNOMIL UNAMIR UNOMUR UNOSOM II UNASOG UNMOT UNAVEM III UNCRO UNPREDEP UNTAET UN Observer Mission in Liberia UN Assistance Mission for Rwanda UN Observer Mission Uganda Rwanda UN Operation in Somalia II UN Aouzou Strip Observer Group UN Mission of Observers in Tajikistan UN Angola Verification Mission UN Confidence Restoration Operation UN Preventive Deployment UN Transitional Authority in East Timor 1993 1993 1993 1993 1994 1995 1995 1995 1995 1999 Sumber: UN Department of Public Information (dikutip dalam A. Jan et al (1995, 94). ANALISIS Dunia dan Isu Pertahanan Pasca Perang Teluk II Ninok Leksono1 PERANG Teluk II yang dilancarkan oleh Amerika Serikat (AS) yang didukung oleh sekutu utamanya, Inggris, berlangsung selama sekitar tiga pekan, mulai dari habisnya batas waktu bagi Saddam Hussein untuk meninggalkan Irak tanggal 20 Maret 2003 hingga jatuhnya ibukota Baghdad 9 April 2003 dan kota-kota di utara, termasuk Tikrit beberapa hari kemudian. Namun, meski pendek, Perang tersebut telah menimbulkan banyak dampak, langsung ataupun tidak langsung. Dampak tersebut juga amat mendalam, khususnya bagi dunia yang terbelah, antara yang mendukung dan menentang serangan pimpinan AS di atas. Artikel ini pertama-tama bermaksud melihat permasalahan keamanan internasional berkaitan dengan perkembangan situasi dunia di awal abad ke-21, khususnya pasca Serangan 11 September 2001 di AS. Berikutnya akan diulas pula sejumlah isu keamanan yang potensial menjadi konflik di masa datang. Melengkapi artikel ini, coba pula dikemukakan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menghadapi situasi keamanan yang banyak mengalami berbagai perubahan dewasa ini, dan seiring dengan itu juga dikemukakan bagaimana hal tersebut direspon oleh kebijakan pembangunan pertahanan. Sifat konflik Bagi AS Serangan 11 September 2001 telah mengubah persepsinya mengenai keamanan nasional. Pandangan bahwa Tanah Air Amerika aman telah diruntuhkan, sehingga pemerintah yang memang berkewajiban melindungi segenap warga terpanggil untuk menempuh 1. Redaktur Senior Kompas dan Pengajar Jurusan HI - FISIP UI Ninok Leksono, Dunia dan Isu Pertahanan 75 langkah apa pun. Ide yang lalu banyak diadopsi oleh penanggung jawab keamanan nasional AS adalah bahwa kalau perlu pihak yang berpotensi mengancam keamanan AS diperangi di tempat asalnya. Kalau perlu AS akan melancarkan serangan semacam itu secara sepihak, tanpa meminta dan tanpa dukungan Dewan Keamanan (DK) PBB sekali pun. Ketika menjelang Perang Teluk II, AS merasa bahwa dukungan yang ia harapkan tidak akan ia peroleh di DK PBB, karena Perancis dan Rusia selaku anggota tetap DK banyak diberitakan akan menggunakan hak veto mereka untuk menghalangi penggunaan kekuatan terhadap Irak, maka AS lalu memilih melakukan aksi sepihak bersama Inggris. Sejumlah kalangan menyebut invasi AS ke Irak sebagai satu perang mendahului (pre-emptive war), sementara kalangan lain menyebutnya sebagai perang pencegahan (preventive war). Perlu dijelaskan di sini, bahwa sesungguhnya perang mendahului dilakukan oleh satu pihak yang bermusuhan dengan menyerang lebih dulu musuh yang sudah menghunus pedang atau mengarahkan rudal ke pihak tadi. Atas dasar itu, argumen perang re-emtif dalam kasus Irak terakhir tampak lemah, karena hampir semua orang tahu Irak tidak – dan tidak punya kemampuan – mengarahkan rudal ke arah wilayah AS. Dengan itu, maka sebenarnya yang dilakukan AS kemarin ini tidak lain adalah melancarkan perang preventif. Karena, kalaupun benar Irak memang bermaksud mengancam AS, atau secara umum negara ini merupakan ancaman bagi adidaya AS, maka ancaman tersebut bisa dikatakan masih merupakan ancaman kecil. Irak – meminjam istilah pengamat militer Hasnan Habib – baru berupa anak macan, belum macan dewasa. Sifat preventif lalu tampak menonjol karena macan tidak diserang ketika ia sudah dewasa atau berbahaya, tetapi justru ketika masih kecil. Ia diserang sekarang, bukan lima tahun lagi, misalnya. Aksi Presiden AS George W Bush terhadap Irak bisa dikatakan sebagai satu hal baru dalam sejarah dunia kontemporer. Apa yang dilakukan AS ini dikhawatirkan akan dijadikan sebagai preseden dalam praktik penyelesaian pertikaian antarbangsa. Memang mungkin saja tidak semua negara yang berniat melancarkan perang preventif bisa menahan kutukan dunia sekuat AS. Tetapi tetap saja perang preventif telah dilihat sebagai satu pilihan solusi bagi penyelesaian konflik modern. Sementara langkah AS di atas juga telah menimbulkan kekhawatiran terhadap sejumlah negara yang sering disebut-sebut AS sebagai pendukung terorisme. 76 Demokrasi & HAM Vol. 3, No. 2, Mei-September 2003 Jadi ramifikasi serangan AS ke Irak terakhir ini menjangkau ke berbagai pihak, mulai dari negara-negara yang melihat tetangga di perbatasannya sebagai musuh seperti India dan Pakistan, hingga Iran dan Korea Utara yang termasuk dalam apa yang sering disebut sebagai bagian dari “Poros Setan”. Sebelum 20 Maret 2003, seperti ada pemahaman, bahwa sejak berakhirnya Perang Dunia II hingga berakhirnya Perang Dingin ada semacam konsensus mengenai penggunaan kekuatan dan bagaimana hal itu harus diatur. Kini dengan aksi AS sebagai preseden, bukannya tidak mungkin satu hari satu kekuatan besar lain melakukan hal yang menimbulkan kecemasan itu. Dikhawatirkan perdamaian relatif yang ada sejak Perang Dunia II yang ditandai dengan penerapan ketat mengenai tata-cara penggunaan kekuatan kini dihadapkan pada tantangan serius.2 Sebelum ini, adanya pembatasan legal bagi penggunaan kekuatan untuk aksi nyata pertahanan diri dan aksi penegakan perdamaian internasional menjadi salah satu alasan utama turunnya jumlah perang antarnegara, meskipun jumlah negara bertambah banyak. Tidak banyak negara yang berani melanggar piagam PBB yang menetapkan persyaratan spesifik bagi penggunaan kekuatan untuk melancarkan aksi preemtif. Dua perkecualian yang menonjol, seperti dicatat oleh Chris Reus-Smidt dari Department of International Relations dari Australian National University di Canberra adalah serangan Israel tahun 1981 ke reaktor nuklir Irak di Osirak dan serangan negara Yahudi ini yang memicu Perang Enam Hari tahun 1967. Kini Doktrin Bush memperkenalkan aspek preventif dan invasi ke Irak merupakan bentuk penerapannya yang pertama. Hal itu dapat dilihat dengan telah dibukanya Kotak Pandora, yaitu di mana orang tak bisa mengetahui di mana limitnya. Yang terjadi, seperti disinggung oleh Prof Hilary Charlesworth dari Centre for International and Public Law ANU, persepsi ancaman benar-benar ada pada si pelaku perang preventif. Ringkas kata, kini di dunia telah tumbuh kekhawatiran bahwa sikap “jalan sendiri semau sendiri” seperti dilakukan oleh AS sudah menjadi semacam realita kehidupan internasional. Negara adidaya ini akan terus bersikap mengabaikan komunitas internasional sejauh itu dirasanya cocok dengan kepentingannya, misalnya saja ketika ia tidak mau tunduk pada Traktat Kyoto yang membatasi pemanasan global. 2. Jane Macartney, Reuters, Singapura, The Jakarta Post, 28/3/03 Ninok Leksono, Dunia dan Isu Pertahanan 77 Keadidayaan besar kemungkinan adalah salah satu alasan mengapa AS mampu bersikap seperti itu. Status itu sendiri ditopang dengan kekuatan ekonomi, sains dan teknologi, pengaruh politik di badan-badan dunia, serta tentu saja keperkasaan dalam militer. Dukungan Militer Perkasa Keperkasaan militer ini lah yang kemudian diperlihatkan dalam Perang Irak terakhir. Senjata berteknologi tinggi (hi-tech) makin besar peranannya. Bahkan karena didukung oleh persenjataan canggih ini pula AS memberanikan diri menerapkan perang digital. Teknologi dan aneka persenjataan terbaru tersedia dalam berbagai pilihan, tetapi jelas bahwa adanya sosok seperti Menteri Pertahanan (Menhan) Donald H Rumsfeld yang pro pada doktrin perang modern menjadi satu elemen pendorong penting bagi terjadinya Perang Teluk 2003 yang sudah sama-sama kita saksikan. Pada dasarnya, teori perang baru yang diyakini Menhan AS ini memberi tekanan besar pada kekuatan udara, komunikasi komputer, dan kekuatan darat yang tidak besar tetapi lincah. Semua unsur di atas melambangkan ketinggian teknologi yang telah dicapai AS. Semenjak bergabung dengan pemerintahan Bush, Rumsfeld memang sudah berbicara tentang “transformasi”, yang ia maksudkan sebagai orientasi pada kekuatan yang lebih ramping dan banyak ditopang oleh teknologi, dan jauh berbeda dengan kekuatan pada zaman Perang Dingin. Ini berbeda dengan apa yang diyakini oleh jenderal status quo, bahwa perang masa depan masih akan dimenangkan dengan cara lama, yaitu dengan daya tembak (firepower) mematikan, dan kekuatan darat yang memadai. Ketika Presiden Bush semakin jelas akan menyerang Irak, maka cetak biru perang yang dicapai adalah konsensus antara Rumsfeld dan Jenderal Tommy Franks. Franks meminta kekuatan konvensional berjumlah 250.000 pasukan tempur dan pendukung. Sementara Rumsfeld mendapatkan persetujuan Franks untuk menggelar pasukan secara bertahap, tidak sekaligus semuanya. Rumsfeld juga mendapat persetujuan untuk menerapkan strategi yang akan melancarkan serangan udara dan darat secara simultan, gerak maju ke Baghdad yang cepat, serta penggunaan secara ekstensif unit-unit operasi khusus. Ketika dilaksanakan di medan tempur, yang diharapkan adalah strategi ini mampu menimbulkan efek “mengejutkan dan menakutkan” (shock and awe). Hanya saja dalam pelaksanaannya tidak semua rencana perang digital ini mulus. 78 Demokrasi & HAM Vol. 3, No. 2, Mei-September 2003 Namun pemikiran baru petinggi pertahanan Amerika ini sebenarnya juga mewakili apa yang telah hidup dalam beberapa tahun terakhir di kalangan penasihat kebijakan pemerintah AS, yang jelas mendukung diberlakukannya serangan preemtif terhadap musuh-musuh Amerika di era menyebar-luasnya isu senjata pemusnah massal. Dalam upaya itu, AS dapat memanfaatkan keunggulannya dalam teknologi tinggi. Antara lain, adalah kemajuan dalam teknologi komunikasi, pengelak radar (stealth), robotik, dan penetapan sasaran (targeting) presisi, yang kesemuanya itu diharapkan bisa bertindak sebagai “pengganda kekuatan” sehingga mengurangi kebutuhan akan tentara darat dan kanon besar.3 Jadi apa yang diuji coba dalam Perang Irak terakhir ini sebenarnya bukan saja kecanggihan militer AS, tetapi keseluruhan filosofi peperangan. Antara lain karena pendekatan Rumsfeld kontras tajam dengan doktrin “kekuatan berlebih” (overwhelming force) yang digagas oleh Jenderal Colin Powell, yang menjelang Perang Teluk 1991 menjabat sebagai Kepala Staf Gabungan. Kalau Powell meminta 550.000 pasukan untuk melancarkan Perang Teluk 1991, Rumsfeld dan koleganya yang sepaham berpendapat, bahwa menggelar pasukan dalam jumlah sangat besar tidak selalu dibutuhkan di era ketika sistem komputasi-jaringan yang kuat dan munisi akurat semakin bisa menggantikan banyak pekerjaan berbahaya. Dari pertarungan ide di atas, maka hasil Perang Irak kemarin memang bisa menentukan nasib visi Rumsfeld, yang diakui memang mendapat tantangan dari banyak kalangan pimpinan militer. Kalau AS bisa menang cepat, maka akan ada langkah untuk mempercepat modernisasi kekuatannya dan membuatnya semakin bersandar pada persenjataan teknologi canggih. Hal itu pada gilirannya juga akan terus memberi berkah rejeki pada industri yang terakhir agak terseok Pameran Persenjataan Canggih Seperti halnya pada Perang Teluk 1991, Perang Teluk 2003 juga mempertontonkan aksi persenjataan berteknologi tinggi. Seperti halnya pada Perang Teluk I, serangan juga dimulai dengan penembakan ratusan rudal jelajah Tomahawk, yang dilakukan serentak bersama pemboman oleh jet siluman (stealth) F-117A Nighthawk. 3. Business Week, 7 April 2003 Ninok Leksono, Dunia dan Isu Pertahanan 79 Kekuatan udara semakin mengokohkan perannya dalam Perang berbasis teknologi tinggi ini, antara lain dengan pengerahan jet-jet baru seperti Super Hornet F/A-18E yang dilengkapi dengan sensor laser kuat dan dapat menetapkan empat sasaran sekaligus. AS juga mengerahkan tiga pesawat pembom dari tiga generasi, mulai dari B-52, B-1, dan B-2 untuk misi pemboman sasaran strategis. Sementara pesawat tempur menguasai udara, dan pembom menghancurkan sasaran militer, kekuatan udara lain juga memberi sumbangan besar, yakni helikopter tempur Apache Longbow yang menjadi ujung tombak bagi gerak maju divisi tank AS. Heli AH-64D yang sering dijuluki heli tempur paling maju di dunia ini – meski sempat ditembak jatuh dalam Perang Irak 2003, konon oleh senapan petani – dapat mengunci 16 tank musuh sebagai sasaran dalam satu waktu. Kekuatan udara kini pun diperkuat dengan pesawat tak berawak (drone) seperti Predator yang diterbangkan di atas sasaran, mengambil citra video medan tempur dan mengirimkannya ke komandan medan tempur serta Komando Sentral AS di Qatar melalui satelit komunikasi. Peran satelit tampaknya juga semakin membesar. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya bom-bom yang dipergunakan, dan mengandalkan panduan satelit. Seperti halnya satelit-satelit GPS mengirim informasi pada bom yang tengah dijatuhkan, mengoreksi arah, dan memandunya ke sasaran. Kekuatan Amerika di Irak dengan demikian memang menikmati semua kemajuan teknologi yang telah dicapai bangsa itu, sehingga gambar besar tentang jalannya perang serta pengorganisasiannya bisa diperoleh secara real-time, dan dengan dukungan komunikasi jaringan, hubungan antara komandan dan pasukan bisa dilakukan dengan kecepatan tinggi. DOKTRIN RUMSFELD 1. Serangan secepat kilat jauh ke dalam wilayah musuh dengan pasukan lebih sedikit tetapi dengan perlengkapan lebih baik. 2. Penekanan pada bom dan rudal berpengaruh presisi untuk melumpuhkan komando dan memaksa musuh menyerah, dan itu dilakukan dengan membatasi korban di kalangan sipil. 3. Penggunaan lebih banyak operasi khusus. 80 Demokrasi & HAM Vol. 3, No. 2, Mei-September 2003 Kebutuhan Pemutakhiran Seiring dengan perkembangan situasi internasional, di mana ada kecenderungan melancarkan aksi sepihak dalam kemasan perang intervensi, serta melalui pengamatan mengenai pola perang modern yang semakin mengandalkan persenjataan teknologi canggih, maka tidak sedikit negara yang kemudian termotivasi untuk melakukan pemutakhiran peralatan militer selain pemutakhiran doktrin pertahanan. Berikutnya juga disadari, bahwa upaya-upaya untuk pemutakhiran peralatan militer tersebut ternyata tidak selamanya semulus seperti diinginkan. Sejumlah faktor ternyata tetap bermain di sini, sehingga meskipun kalangan industri amat berharap bisa menjual produk mereka, akan tetapi pemerintahnya tidak selalu mewujudkan rencana penjualan tersebut. Ternyata prinsip-prinsip yang tetap berlaku dalam banyak transfer senjata adalah sebagaimana dikemukakan oleh Andrew Pierre, bahwa hal itu bukan hanya sekadar transaksi biasa, tetapi lebih banyak terkait dengan hubungan politik. Jadi kedekatan hubungan antara pemasok (supplier) dan penerima (recipient) amat menentukan kelancaran transfer senjata. Perubahan politik amat mewarnai transfer senjata. Polandia relatif belum lama lepas dari pengaruh Blok, namun ketika kredensial demokratiknya memuaskan AS, maka transfer empat skadron F-16 pun bukan hal yang sulit. Beda halnya dengan Indonesia, meski dikenal dekat dengan AS, namun setelah beberapa kali dalam kurun satu dekade terakhir, Indonesia terganjal permintaannya untuk mendapatkan transfer perlengkapan dari AS. Realita ini sesungguhnya bernuansa paradoks dengan trend yang ada dalam perdagangan senjata internasional. Ketika industri perlengkapan militer dunia masih terpusat pada sejumlah negara industri maju – dalam hal ini AS dan negara-negara Eropa – maka pilihan pun tidak banyak bagi negara-negara yang menginginkan senjata. Ini lah kondisi yang disebut sebagai seller’s market atau pasarnya penjual. Dalam kondisi ini, penjual leluasa menetapkan harga dan berbagai persyaratan lain. Memasuki dekade 1980-an, sains dan teknologi mulai mengalir ke negara-negara industri baru di Asia seperti Malaysia dan Singapura, dan bahkan di negara berkembang seperti Indonesia. Bila platform senjata utama seperti pesawat tempur umumnya masih dikuasai oleh negara-negara industri maju, di lain pihak senjata seperti senapan serbu atau kapal patroli cepat sudah bisa dibuat oleh negara industri baru dan negara berkembang. Ninok Leksono, Dunia dan Isu Pertahanan 81 Bahkan harus dicatat di sini, bahwa di antara negara industri maju itu sendiri juga terjadi persaingan yang semakin sengit. Situasi pasca Perang Dingin, negara-negara bekas Blok Barat mencoba memperoleh dividen perdamaian. Hal ini ditandai dengan dilakukannya pengurangan anggaran belanja militer. Situasi tersebut membuat daya beli internal susut, dan daya jual produk makin tinggi. Konsekuensinya, antara sesama negara maju tadi harus bersaing ketat memperebutkan pasar. Situasi ini juga akan membuat pasar senjata internasional menjadi lebih cair, di mana konsumen punya lebih banyak pilihan. Trend pasar pun kemudian akan bergeser dari seller’s market ke buyer’s market atau pasar pembeli. Tetapi rupanya sifat pasar yang seperti itu masih tetap belum bisa mengubah ciri dasar transfer senjata, yaitu yang menyangkut jauhdekatnya hubungan antara penjual-penerima. Sementara dari segi pembeli, urusan pembelian senjata juga ternyata bukan hanya menyangkut persetujuan penjual, tetapi berikutnya juga tersedianya dana pembelian. Ditawarkan Tapi Tak Selalu Bisa Dibeli Setiap kali usai satu perang, maka satu pihak yang ingin mendapat keuntungan adalah industri senjata yang berkinerja baik, khususnya di pihak pemenang. Ilustrasi paling spektakuler mengenai hal ini adalah di Pameran Kedirgantaraan Paris tahun 1991 yang dilaksanakan kurang dari empat bulan dari Perang Teluk I. Di sana, jet siluman (stealth) yang mengawali Perang itu datang dengan profil tinggi, sementara jet Tornado Inggris, demikian pula Jaguar Perancis yang bercat kuning coklat tampak di sana-sini gosong tersengat cuaca gurun yang amat terik. Ada juga rudal Patriot. Dengan dipromosikan sebagai combat proven – atau terbukti unggul dalam pertempuran – sederet senjata lalu memang mengundang daya tarik bagi pembeli, khususnya dari negara-negara berkembang yang merasa sudah cukup punya rejeki atau yang sedang dihadapkan pada satu tantangan keamanan. Dalam hal Perang Teluk 1991, pembeli utama adalah negara-negara Teluk sendiri yang dari dekat mendengar kehebatan persenjataan tersebut, dan selain itu – khususnya Kuwait – juga ingin menjadikan pembelian perlengkapan militer AS sebagai salah satu bentuk ucapan terima kasih kepada negara adidaya itu karena telah membantunya mengusir Irak Saddam Hussein. 82 Demokrasi & HAM Vol. 3, No. 2, Mei-September 2003 Tetapi sekali lagi meskipun persaingan di antara pemasok menguat, hal itu tidak serta-merta diikuti dengan penjualan bebas. Apa yang dialami Indonesia boleh jadi merupakan satu contoh yang gamblang tentang dimensi non-ekonomi atau perdagangan dari penjualan senjata. Perubahan orientasi politik pemerintahan AS yang cenderung mengaitkan masalah seperti HAM pada transfer senjata membuat Indonesia tidak bisa membeli jet F-5E dari Yordania menyusul pecahnya Insiden Dili tahun 1991. Keinginan untuk membeli F-16 tambahan pun pada paruh kedua tahun 1990-an tak diluluskan, hal yang membuat Indonesia pada tahun 1997 menanda-tangani persetujuan dengan Rusia untuk membeli jet Sukhoi. (Persetujuan ini sendiri kemudian dibatalkan menyusul pecahnya krisis moneter tahun 1997 yang memburuk pada tahun 1998.) Pengalaman makin seretnya transfer perlengkapan militer dari AS bertambah buruk lagi menyusul pecahnya aksi kekerasan pasca Jajak Pendapat Timor Timur tahun 1999. Setelah itu AS, juga negara-negara Eropa Barat, menerapkan embargo terhadap Indonesia menyangkut penjualan perlengkapan dan suku cadangnya. Keadaan ini amat memukul Indonesia, baik secara psikologis-politis, maupun secara kemampuan militer. Tidak saja jet F-16, tetapi bahkan jet Hawk yang buatan Inggris pun ikut terkena karena menggunakan avionik buatan Amerika. Lebih buruk lagi, embargo juga mengenai pesawat angkut Hercules, padahal di masa Indonesia banyak terkena konflik internal lima tahun terakhir, pesawat ini banyak digunakan untuk menjalankan misi kemanusiaan (civic/humanitarian mission). Selain menyangkut persepsi mengenai HAM, ganjalan dari pemasok lazimnya dikaitkan dengan pertimbangan politik, misalnya pembelian tersebut lalu akan memicu destabilisasi keamanan, meskipun hal ini sering juga tidak berlaku. Salah satu contohnya adalah, akuisisi senjata Amerika dan Perancis oleh Taiwan. Dalam arti, meski RRC tidak senang dengan pembelian Taiwan tersebut, tetapi penjualan jet Mirage dari Perancis dan F-16 Amerika tetap dijalankan. Tampak bahwa dari pihak pemasok sendiri terdapat kebijakan yang dipandang dari kacamata umum bisa terkesan kurang konsisten. Artinya, pertimbangan ekonomi perdagangan untuk mendukung industri domestik lebih mengemuka dibandingkan dengan pertimbangan politik yang mengakomodasi ketidak-senangan RRC terhadap penjualan di era 1990-an tersebut. Ninok Leksono, Dunia dan Isu Pertahanan 83 Sebaliknya pemasok lain juga tidak peduli dengan kerisauan AS. Betapa pun banyak protes AS disampaikan terhadap Rusia yang menjual pembangkit listrik nuklir terhadap Iran, yang dikhawatirkan bisa sekalian untuk memproduksi bahan pembuat bom nuklir, Rusia tetap jalan terus dengan penjualannya ke Iran. Hal sama juga terjadi dengan pengapalan rudal balistik Korea Utara ke sejumlah negara Timur Tengah, atau transfer teknologi misil RRC ke Pakistan. Pengawasan Makin Ketat Transfer senjata boleh jadi tetap akan mengikuti idiom khasnya hingga kapan pun, seperti yang menyangkut pola hubungan pemasokpenerima. Tetapi khususnya menyangkut senjata pemusnah massal – dalam hal ini nuklir, biologi, dan kimia – negara seperti AS tampaknya akan semakin ketat. Menyusul Serangan 11 September 2001, AS merasa bahwa serangan dengan metode paling tak terduga – seperti menjadikan pesawat penumpang sebagai rudal – pun akan terus mengancam dirinya. Tetapi tetap yang dikhawatirkan paling serius adalah serangan yang menggunakan senjata pemusnah massal. Di sini pengawasan dilakukan dengan mengekang tidak saja bomnya, tetapi juga sarana pelontarannya. Untuk bomnya, pengetatan pengawasan dilakukan dengan membatasi transfer atau penggunaan reaktor dan fasilitas nuklir yang berkapasitas memproduksi material bahan bakar bom, seperti yang dimiliki Korea Utara di Yongbyon. Meski sejauh ini AS dan Korea Utara masih membuka pintu dialog, tetapi pada pekan ketiga Mei 2003 AS sudah menyuarakan niat untuk bersikap lebih tegas terhadap Pyongyang. Gambaran yang bisa terjadi kalau sampai perundingan tidak produktif dan situasi memburuk, di mana Korea Utara semakin meningkatkan ancaman militernya, adalah serangan preemtif A.S. dengan sasaran khusus fasilitas nuklir Yongbyoan. Dalam kaitannya dengan sarana pelontaran (delivery), sebenarnya sejak tahun 1987 negara-negara besar sudah mendirikan apa yang dinamakan Regim Pengawasan Teknologi Rudal (MTCR, Missile Technology Control Regime). Regim ini jelas membuat banyak negara yang ingin mengembangkan teknologi peroketan pun jadi kesulitan, karena memang teknologi roket bersifat ganda, bisa sipil untuk peluncuran satelit pemantau cuaca, atau untuk militer guna mengangkut hulu ledak konvensional atau pemusnah massal. 84 Demokrasi & HAM Vol. 3, No. 2, Mei-September 2003 Tantangan Teknologi Maju Perang modern seperti Perang Teluk 1991 dan lebih-lebih Perang Irak 2003 memperlihatkan, bahwa persenjataan teknologi canggih semakin besar peranannya dalam membantu memenangkan perang. Dukungan teknologi – seperti telah diuraikan di atas – tidak saja diwujudkan dalam bom-bom yang semakin pintar, karena ia dipandu kesasaran dengan sinyal satelit, tidak jatuh bebas, tetapi juga jaringan komunikasi untuk mendukung peperangan. Harus diakui, bahwa kemajuan teknologi informasi-komunikasi (ICT) telah dieksploitasi seoptimal mungkin oleh AS dalam Perang Teluk 2003. Dengan apa yang disebut “Internet Taktis”, maka Komando Sentral bisa memperoleh informasi semua medan tempur seketika, prajurit di lapangan pun – dengan peralatan mobile PDA (Personal Digital Assistance) - juga bisa mendapat informasi terkini menyangkut perkembangan pergerakan kekuatan. Jaringan komputer – meski tidak sepenuhnya aman – telah menjadi alas bagi dikembangkannya doktrin perang digital. Semula memang hal ini amat dikhawatirkan. Tetapi dengan bisa diselesaikannya kampanye perang Irak dalam tempo tiga pekan, dan dengan jumlah pasukan lebih sedikit dibanding jumlah pasukan pada Perang Teluk 1991, maka keyakinan terhadap efektivitas sistem berbasis ICT mendapat pijakan kuat (vindicated). Di sini pun lagi-lagi AS berada dalam posisi paling depan, karena bisa dikatakan bahwa ICT, komputer dan Internet lahir dan berkembang pesat di negeri adidaya itu. Sementara negara-negara berkembang justru semakin tidak mampu menjangkau kemajuan yang ada, bahkan terjadi kesenjangan digital (digital divide). Jadi, sebagai penutup dapat dikemukakan di sini, bahwa dihadapkan pada situasi internasional, khususnya lingkungan keamanan yang berubah secara fundamental, negara-negara berkembang memang menghadapi tantangan baru yang tidak sepenuhnya bisa direspons secara memadai, baik yang berkaitan dengan penguasaan teknologi, pemerolehan persenjataan canggih, maupun penyediaan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan. Memang tidak sepenuhnya hal itu kesalahan negara berkembang, karena negara-negara maju memang dalam perkembangannya cenderung menerapkan sistem dan aturan yang makin ketat bagi penyebar-luasan teknologi, khususnya yang berkaitan dengan pertahanan. TELAAH BUKU Bangsa: Antara Bayangan dan Realitas Rahadi T. Wiratama Benedict Anderson, Imagined Communities, Komunitas-Komunitas Terbayang, Pengantar: Daniel Dhakidae, Yogyakarta: Insist bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, liii + 336 halaman, termasuk Kepustakaan dan Indeks, 2001 Telah lama kebangsaan memperoleh serangan gencar dari berbagai aliran pemikiran dan kepentingan. Cukup unik bahwa kaum Marxis maupun para kapitalis berskala global – dua entitas yang saling bertentangan – memiliki kecurigaan yang sama terhadap segala sesuatu yang diasosiasikan dengan “bangsa,” “kebangsaan” dan “negara bangsa,” tentu saja dengan alasannya masing-masing. Di mata kaum Marxis kebangsaan — yang kemudian menjadi salah satu dasar bagi munculnya chauvinism itu — merupakan penghalang bagi terciptanya solidaritas kemanusiaan internasional. Pada tahap ini, kalangan Marxis memiliki posisi yang kurang-lebih sama dengan kaum humanis-liberal. Lebih dari itu, kaum Marxis – dan kali ini berbeda dengan posisi kaum humanis-liberal – beranggapan bahwa kebangsaan, yang sering kali menjelma ke dalam bentuk nation-state itu, hanya akan menghasilkan sebuah organisasi kekuasaan yang berfungsi untuk mereproduksi relasirelasi kapitalistis. Sementara itu, di sisi yang lain, bagi kalangan kapitalis raksasa paham kebangsaan yang memunculkan kedaulatan teritorial itu merupakan penghalang bagi ekspansi modal. Betapapun ide dan praktek bangsa-kebangsaan-nation state kerap kali memperoleh serangan dari berbagai spektrum ideologi dan kepentingan, namun pada abad ke-20 dan ke-21 ini fenomena semacam 86 Demokrasi & HAM Vol. 3, No. 2, Mei-September 2003 itu tetap muncul sebagai fakta yang sulit ditolak, sejak ia muncul untuk pertama kalinya di daratan Eropa pada abad ke-18. Lalu, mengapa gejala bangsa, kebangsaan dan negara-bangsa – di tengah-tengah kritik atas fenomena itu – tetap bertahan hingga kini? Mengapa kematian bangsakebangsaan-negara bangsa yang pernah diramalkan sebelumnya tak kunjung terwujud—bahkan di era kekinian yang, konon, tak lagi mengenal batas-batas teritorial? Dan, mengapa pula kajian tentang aspekaspek kebangsaan tetap memiliki daya pikat yang kuat bagi ilmu-ilmu sosial-humaniora? Sederetan pertanyaan pokok itulah pada akhirnya mendorong Benedict Anderson – Profesor Ilmu Politik asal Universitas Cornell, AS – untuk melakukan upaya pelacakan terhadap asal-usul nasionalisme. Dengan kata lain, melalui buku ini, Anderson bermaksud untuk menemukan jawaban atas pertanyaan: mengapa fenomen bangsakebangsaan-negara bangsa memiliki daya tahan yang luar biasa? Berbeda dengan para pemikir klasik tentang nasionalisme yang sebelumnya kerap menjadi referensi, Anderson rupanya memiliki rumusan tersendiri tentang bangsa. Dalam pandangan Anderson, bangsa atau nation merupakan sebuah komunitas politik terbayang—imagined political community. Ia dibayangkan sebagai sesuatu yang bersifat terbatas (limited) secara inheren, karena pasti ada batas-batas teritorial dengan bangsa-bangsa lain di sekitarnya; berdaulat (sovereign), karena para pembayangnya menganggap perlu ada perlindungan; dan akhirnya ia dibayangkan sebagai sebuah komunitas (community), karena para anggotanya memiliki rasa persaudaraan antar mereka. Ketika internalisasi bayangan tentang bangsa mencapai titik kul minasinya, menurut pengamatan Anderson, para anggota komunitas itu bersedia – jangankan mengorbankan orang lain – bahkan untuk mengorbankan dirinyapun orang rela demi apa yang mereka hayati sebagai komunitas-komunitas terbayang itu. Namun Anderson juga tak lupa menambahkan bahwa munculnya print capitalism – yang ikut menyebarluaskan “kesadaran bersama” pada beberapa abad sebelumnya itu – telah memberikan dasar bagi munculnya gagasan komunitaskomunitas terbayang di daratan Eropa. Lebih dari itu, Anderson meyakini adanya unsur-unsur kebudayaan dari para pembayang bangsa yang lebih dulu hadir. Faktor inilah yang, menurut Anderson, membuat konstruk komunitas-komunitas terbayang memiliki watak antropologis. Dalam buku – yang edisi aslinya diterbitkan tahun 1983 ini – Anderson mengawali pemaparannya dengan mengetengahkan konflik Rahadi T. Wiratama, Bangsa: Antara Bayangan dan Realitas 87 bersenjata antar tiga negara yang berdiri di atas landasan ideologi Marxisme-Leninisme di tahun 1978-1979: RRC dan Republik Demokratik Kamboja di satu sisi versus Republik Sosialis Vietnam di sisi lain. Meski maksud pemaparan itu tidak dinyatakan secara eksplisit, namun – melalui ilustrasi pertikaian ketiga negara yang mengaku sebagai pewaris ajaran Marxis-Leninis itu – pembaca “digiring” untuk memberikan tafsiran: bahwa kaum Marxis-Leninis yang, konon, memiliki solidaritas atas dasar persaudaraan internasional toh akhirnya – dan ternyata – dapat masuk ke dalam bentuk pertikaian antar sesama mereka sendiri atas nama kepentingan nasionalnya masing-masing. Soalnya adalah, dapatkah masing-masing negara itu memberikan label kepada para prajurit yang tewas di medan tempur itu sebagai “gugur dalam membela Marxisme-Leninisme?” Dari ilustrasi semacam itu secara karikatural Anderson mengajukan pertanyaan, bagaimana mungkin kita dapat membayangkan sebuah tugu peringatan dari sebuah makam yang bertuliskan: “Marxis Tak Dikenal” ataupun “Liberal Tak Dikenal,” hanya sekadar untuk menunjukkan ideologi-politik yang dianut oleh mereka yang gugur di medan tempur? Dari persoalan yang diajukan Anderson ini, muncul pertanyaan lebih lanjut: manakah yang lebih absurd? Pandangan paham kebangsaan ataukah pandangan kaum Marxis dan Liberal? Lalu, apa signifikansi dari hasil pelacakan Anderson atas komunitaskomunitas terbayang itu terhadap polemik teoritis antara para pembayang bangsa dengan lawan-lawannya? Salah satu jawabannya adalah bahwa ketika berbagai aliran ideologi dan pemikiran mendera nasionalisme sebagai sebuah bentuk absurditas, kenyataan – sebagaimana yang ditunjukkan Anderson – justru memberikan dasar untuk menjungkirbalikkan keyakinan yang selama ini hampir tak tergoyahkan itu. Sebab, kaum Marxis maupun Liberal toh akhirnya tetap merupakan anggota (baca: warganegara) dari sebuah komunitas besar (baca: bangsa) betapapun mereka menolaknya. Kaum Marxis maupun Liberal pasti akan mengalami kesulitan untuk menemukan seorang manusia di muka bumi ini yang tidak memiliki tanah air, betapapun ia – seandainya memang ditemukan jenis manusia semacam ini – mungkin lebih merasa sebagai anggota umat manusia sedunia daripada anggota bangsa atau negara tertentu. Ini berarti bahwa kaum Marxis maupun Liberal yang membayangkan persaudaraan umat manusia sedunia tanpa tanah air ternyata tidak kalah absurdnya dengan para pembayang bangsa. Dengan 88 Demokrasi & HAM Vol. 3, No. 2, Mei-September 2003 demikian, karya Anderson ini secara provokatif membangkitkan pemahaman baru bahwa baik kaum Marxis maupun Liberal tidak perlu menjadi naif dalam memandang nasionalisme hanya karena mereka meyakini – dan sekaligus berharap – tiadanya garis demarkasi teritorial yang menyekat solidaritas dan persaudaraan antar manusia sedunia, sebagaimana – di sisi yang lain – sikap curiga dan naif yang juga sering kali dianut oleh para pembayang bangsa terhadap “humanisme universal” versi Marxisme maupun Liberalisme. Namun, lepas dari persoalan dan polemik antara para pembayang bangsa dengan lawan-lawan politiknya itu, rangkaian logic yang menghubungkan antara “bangsa,” “kebangsaan” dan akhirnya: “negara bangsa” ternyata juga mengandung problematiknya sendiri. Terlebih ketika hubungan itu disederhanakan menjadi “bangsa” dan “negara”— dua entitas yang secara awam kerap dipahami sebagai kesatuan yang tidak bermasalah. Dalam pengantarnya di buku ini Daniel Dhakidae – dengan mengambil contoh Jerman pada era the Third Reich dan Indonesia pada masa Orde Baru – mengungkapkan bahwa justru di sanalah letak kekisruhan logic yang mendasari hubungan antara bangsa dengan negara. Proses dari bangsa menjadi negara – sebagaimana ditunjukkan oleh banyak kasus – sering kali mengalami distorsi. Sebab ketika banyak pihak ikut andil dalam mewujudkan komunitas-komunitas terbayang, proyek itu akhirnya justru jatuh ke tangan negara—suatu fenomen yang pada dasarnya juga disadari oleh Anderson sendiri. Sebagaimana dikemukakan Anderson, penyelewengan komunitaskomunitas terbayang ke dalam bentuk-bentuk nasionalisme resmi, nasionalisme imperial ataupun nasionalisme rasis – yang anti kemanusiaan itu – sesungguhnya merupakan lawan dan sekaligus “anomali” dari apa yang oleh Anderson dinyatakan sebagai paham kebangsaan berwatak kerakyatan yang lebih dulu hadir. Bentuk-bentuk nasionalisme anti kerakyatan itulah yang kerap memberikan “sumbangan” terhadap berbagai tragedi kemanusian dalam wujud holocaust dan genocide, sebagaimana dipraktikkan oleh kaum ultra-nasionalis Jerman, fasis Itali dan militeris Jepang semasa Perang Dunia II, serta kaum rasis Serbia di era 90-an. Pada tahap ini, komunitaskomunitas terbayang akhirnya terperosok menjadi fasisme atau statenationalism. Dari sisi ini, bayangan tentang bangsa – yang oleh para pembayangnya sama sekali jauh citra kekuasaan dan kekerasan itu – justru sering dijadikan klaim negara fasis untuk membenarkan kehadiran Rahadi T. Wiratama, Bangsa: Antara Bayangan dan Realitas 89 dan tindakannya. Di masa Orde Baru, misalnya, makna kebangsaan – di bawah jargon “demi persatuan dan kesatuan” – direduksi menjadi stabilitas nasional dengan segala perangkat keras dan lunaknya. Dengan demikian, proyek komunitas-komunitas terbayang – yang semula dirintis dan dikerjakan oleh para pembayang yang bernama “bangsa” itu – telah direbut dan dibelokkan sedemikian rupa oleh kekuatan-kekuatan yang lebih besar (baca: negara), apalagi jika tidak ditujukan dalam rangka dominasi dan hegemoni. Pada tahap ini muncul suatu ironi, yakni ketika generasi para pembayang bangsa – yang menurut Anderson, berideologi kerakyatan itu – harus menyaksikan karya ciptanya menjadi sumber “legitimasi” bagi pihak lain untuk menciptakan mesin-mesin pembunuh. Dengan kata lain, sebagian dari rangkaian tragedi kemanusiaan yang mengisi lembar-lembar sejarah moderen umat manusia itu ternyata berhubungan erat dengan soal bangsa-kebangsaan-negara bangsa. Pada titik inilah muncul sebuah petaka: yakni ketika proses pembayangan komunitas yang pada mulanya bersifat antropologis (baca: kebudayaan) itu kemudian berubah menjadi proses yang bersifat politis (baca: kekuasaan). Jika itu yang menjadi duduk perkaranya, maka bukankah gejala bangsakebangsaan-negara bangsa justru vis-à-vis dengan gagasan penguatan masyarakat sipil, penegakkan demokrasi dan penghormatan atas HAM yang kini juga tengah diperjuangkan di berbagai negeri? Oleh sebab itu, dapat dimengerti apabila sampai hari ini kalangan Marxis maupun liberal-demokrat tetap mencurigai kebangsaan dengan segala raison détre dan manifestasinya. Namun, lepas dari kritik yang memang patut dilakukan untuk menilai buku ini, Anderson pada dasarnya telah menawarkan perspektif baru dalam memahami munculnya fenomen kebangsaan. Cara Anderson memahami munculnya asal-usul kebangsaan dari sudut pandang subyek – yang oleh Daniel Dhakidae disebut sebagai anthropological in nature itu — ternyata memiliki daya eksplanatif tersendiri. Oleh sebab itu pula karya Anderson ini memiliki pengaruh yang cukup kuat – dan sekaligus menyulut serangkaian polemik — dalam ilmu-ilmu sosial-humaniora kontemporer, terutama di bidang cultural studies. Tidaklah mengherankan jika buku ini telah diterjemahkan ke dalam lebih dari duapuluh bahasa. Keseriusan Anderson – yang berlatar belakang sebagai ilmuwan politik ahli Indonesia itu – dalam melakukan eksplorasi atas asal-usul komunitas-komunitas terbayang itu telah 90 Demokrasi & HAM Vol. 3, No. 2, Mei-Juli 2003 mendorongnya untuk menjelajah lorong waktu (menjangkau hingga abad ke 13), memasuki berbagai ruang (benua, kawasan dan negeri), serta mengkaji berbagai sumber literatur yang amat bervariasi: mulai dari sejarah, sosiologi, antropologi, sastra/linguistik hingga arsitektur, teologi, filsafat dan ekonomi. Atas dasar itu, cukup beralasan jika karya Anderson – yang ingin merangkai hubungan logic antara pembayang dengan sosok bayangannya di satu sisi, serta aktifitas kebudayaan untuk mewujudkan bayangan tentang bangsa di sisi lain itu – dapat dinilai sebagai “artefak” diskursus antropologi-politik yang menawarkan metoda dan rekonstr uksi pemaknaan bar u terhadap asal-usul bangsakebangsaan-nation state. 91 BIODATA PENULIS Dewi Fortuna Anwar, Direktur Program dan Riset, The Habibie Center, Deputi Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusian (IPSK), LIPI, Anggota Dewan Direktur Center for Information and Development Studies (CIDES) Riza Sihbudi, Ahli Peneliti Utama dan Kepala Bidang Perkembangan Politik Internasional pada Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI); Dosen Pasca Sarjana Universitas Indonesia (UI) Program Kajian Timur Tengah dan Islam; Ketua Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES) Jakarta; dan, Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI). Philips J. Vermonte, Peneliti Departemen Hubungan Internasional Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Ninok Leksono, Redaktur Senior Kompas dan Pengajar Jurusan HI – FISIP UI Rahadi T.Wiratama, Peneliti di CESDA-LP3ES Demokrasi & HAM Vol. 3, No. 2, Mei-September 2003 FORMULIR BERLANGGANAN SAYA BERMINAT BERLANGGANAN Nama Mulai Edisi : .................................................................................................. : .................................................................................................. : .................................................................................................. Mohon dicatat sebagai pelanggan Jurnal Demokrasi dan HAM dan mohon dapat dikirim ke alamat saya: Alamat .................................................................................................. Pekerjaan Telepon/Fax : .................................................................................................. : .................................................................................................. : .................................................................................................. .................................................................................................. Instansi Alamat kantor : .................................................................................................. .................................................................................................. Harga Langganan 2 Edisi: Rp. 34.000,(termasuk disc 15%). 4 Edisi: Rp. 60.000,(termasuk disc 25%). • Beri tanda pada kolom yang Anda pilih. • Harga sudah termasuk ongkos kirim untuk Jabotabek. • Luar Jabotabek dikenakan biaya kirim via jasa Pos Rp. 5.000,per eksemplar. • Harga Eceran Rp. 20.000,per eksemplar Pembayaran dimuka: Transfer ke Bank Mandiri Cabang Jakarta Kemang Raya, a/n Yayasan The Habibie Center • a/c 126.0002195401 (mohon bukti transfer difax bersamaan formulir ini) .................................................................................................. ................................., ......................... Tandatangan: _____________________ f a x k e : ( 0 2 1 ) 7 8 1 7 2 1 2 • a ta u k i r i m k e : J l . K e m a n g S e l a ta n N o . 9 8 , J a k a r ta 1 2 5 6 0 , Te l p . ( 0 2 1 ) 7 8 1 7 2 11 92