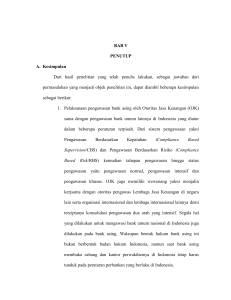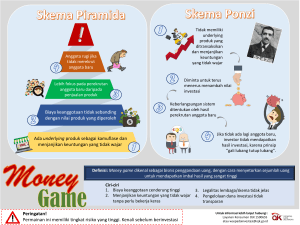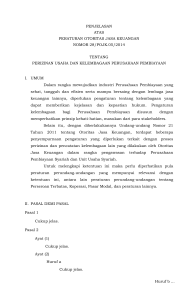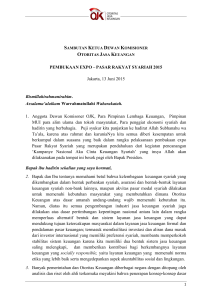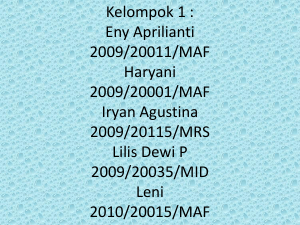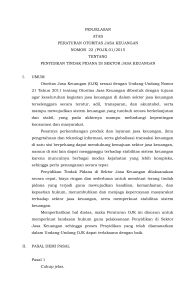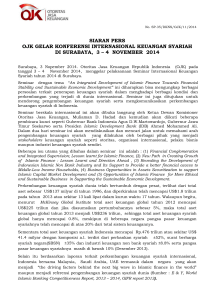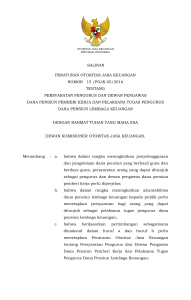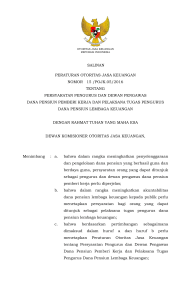1 Mengapa OJK 1 Oleh Arianto A. Patunru Dosen FEUI, Peneliti
advertisement

Mengapa OJK 1 Oleh Arianto A. Patunru Dosen FEUI, Peneliti Senior LPEM-­FEUI Masih cukup segar dalam ingatan kita perdebatan-­‐perdebatan seputar penyelamatan Bank Century beberapa tahun lalu. Telinga kita dipaksa akrab dengan berbagai istilah dan semantik seperti “krisis keuangan”, “krisis ekonomi” “bank gagal”, “dampal sistemik”, dan lain-­‐lain. Memang tak ada batasan atau definisi yang tegas antara “krisis keuangan” dan “krisis ekonomi”. Jamaknya, “krisis keuangan” mengacu pada kondisi jatuhnya indikator-­‐indikator makro keuangan dalam waktu bersamaan atau hampir bersamaan, disertai dampak menjalar yang cepat. Sementara “krisis ekonomi” cakupannya lebih luas daripada sekedar keuangan. Jika krisis keuangan berkaitan dengan arus uang yang macet, sehingga likuiditas menjadi susah; maka krisis ekonomi mencakup inflasi yang sangat tinggi, pertumbuhan yang negatif, dan seterusnya. Krisis ekonomi 2008 berawal dari krisis keuangan. Ia adalah situasi gagal-­‐bayar kredit perumahan di Amerika Serikat secara masif; yang kemudian memberatkan sektor perbankan, keuangan, dan pasar modal. Ini adalah krisis keuangan. Namun, sembari memberi dampak kepada dimensi makro lainnya, ia berubah menjadi krisis ekonomi, dan bahkan menyebar cepat, termasuk ke negara-­‐negara lain. Atau yang lalu kita sebut “dampak sistemik”. Bagaimana sebuah institusi keuangan seperti bank dapat mengakibatkan dampak sistemik? Mengukurnya tentu susah sekali. Tetapi yang perlu diingat, dalam kondisi krisis, sekecil apapun sebuah bank, ketika gagal, ia bisa menimbulkan dampak psikologis berantai. Saat rumor tentang potensi gagalnya suatu bank menyebar, nasabah bisa menjadi kuatir dan secara kolektif melakukan rush ke bank-­‐bank (buru-­‐buru menarik tabungannya). Hal ini bisa berubah menjadi bank panic yang lalu menyebar dengan lebih cepat lagi dan merontokkan keseluruhan industri perbankan lalu perekonomian – sehingga wajar disebut “potensial berdampak sistemik”. Jika kemudian ada insentif untuk melarikan dana ke luar negeri (mis. karena jaminan di luar lebih bagus), maka kemungkinan ini semakin besar. Di sini, istilah “dampak sistemik” memang juga bukan mengacu kepada teori, tapi lebih kepada praktik perbankan, sebagaimana halnya istilah “bank gagal”. Namun permainan semantik sungguh tidak semestinya menjadi priotitas ketika bahaya sesungguhnya adalah krisis yang sedang menggulung. Perdebatan apakah sebuah bank gagal dapat “berdampak sistemik” atau tidak juga tak lepas dari kondisi pada saat yang bersesuaian. Dalam masa krisis, tentu potensi itu menjadi lebih besar lagi. “We have been here before”, kata Reinhart dan Rogoff dalam buku best-­seller mereka, This Time is Different (2009). Meneropong krisis demi krisis sejak era Cina abad 12 dan Eropa abad pertengahan hingga krisis sub-­‐prime AS tahun 2007, mereka mengingatkan bahwa sudah terlalu sering kita mengalami masalah yang sama. Negara-­‐negara dilanda berbagai jenis kemelut keuangan. Sovereign 1 Tulisan ini dimuat di mingguan TEMPO edisi 19-­‐25 Maret 2012 1 default atau gagalnya sebuah pemerintahan membayar hutang, krisis perbankan di mana sektor perbankan yang mengalami insolvency (tak mampu bayar hutang), dan krisis nilai tukar di mana mata uang suatu negara terjun bebas tak terkendali. Dan tak sedikit yang default atau bangkrut. Pada masa-­‐masa awal pendiriannya, Prancis pernah bangkrut delapan kali. Spanyol telah bangkrut 13 kali sebelum abad ke-­‐19. India dan Indonesia pernah bangkrut tahun 1960an. Kita juga telah menyaksikan krisis yang mengglobal: Great Depression tahun 1930an dan GFC (Global Financial Crisis) yang mulai tahun 2007 lalu. Pesan Reinhart dan Rogoff jelas: perlu pengaturan, pengawasan, dan koordinasi yang lebih baik. Tak bisa kita selalu berdalih bahwa kali ini krisisnya beda, “this time is different”; yang dibutuhkan adalah sistem yang lebih kuat untuk menghadapi problem yang sesungguhnya sama sejak delapan abad yang lalu. Kita bersyukur bahwa Indonesia berhasil melewati krisis GFC 2007/2008 dengan cukup baik. Sukar untuk menghitung dengan pasti berapa rupiah yang kita selamatkan. Namun perbandingan yang mungkin relevan adalah dengan krisis AFC (Asian Financial Crisis) 1997/1998. Pada saat itu perekonomian Indonesia jatuh dari 6% ke -­‐13%. Sementara sebagai dampak krisis GFC, perekonomian Indonesia jatuh dari 6% ke 4% (di saat hampir semua negara maju terperosok ke dalam resesi, demikian juga negara-­‐negara tetangga yang bertumbuh negatif). Kerugian Indonesia dari krisis Asia 1997/1998 dihitung dari potensi pertumbuhan yang hilang adalah sekitar US$ 46 miliar dalam setahun, sementara krisis global (yang skalanya lebih besar) “hanya” sekitar US$ 19 miliar (McLeod dan Patunru 2009). Namun kita juga masih ingat, upaya penyelematan ekonomi Indonesia dalam menghadapi GFC mencakup keputusan kontroversial atas Bank Century – yang sampai saat ini masih dipermasalahkan. Kita tentu tidak bisa memastikan apakah keputusan tersebutlah yang menyelamatkan Indonesia, atau kebijakan-­‐ kebijakan yang lain. Yang pasti, kita berhasil menghindari “dampak sistemik” dalam sektor keuangan. Berkaca pada kasus Bank Century dan juga beberapa kasus lain (misalnya Bank Bali), kita mafhum pentingnya pengawasan dan koordinasi. Anwar Nasution mengingatkan bahwa di tengah lemahnya koordinasi antara Bank Indonesia dan Bapepam-­‐LK telah luput, misalnya, keterkaitan antara Bank Century, PT Antaboga Delta Sekuritas, PT Century Mega Investindo, dan PT Century Super Investindo (Kompas, 8/11/2012). Juga kita kuatir, dengan absennya sistem atau perangkat otoritatif, pengambilan keputusan akan selalu bersifat diskresioner. Dan tuntutan demi tuntutan akan dating pasca keputusan – terlepas dari apakah keputusan tersebut telah menyelamatkan perekonomian atau tidak. Kita jengah dengan akrobat politik menghakimi keputusan yang justru sangat strategis. Padahal krisis mungkin datang lagi. Bahkan, krisis Eropa yang saat ini masih berlangsung mulai menjalar ke wilayah Asia. Maka kita menyambut OJK, Otoritas Jasa Keuangan yang sebentar lagi terbentuk. Ia – bersama dengan JPSK (Jaringan Pengaman Sistem Keuangan) -­‐ adalah upaya yang baik dalam rangka “pengaturan, pengawasan, dan koordinasi yang lebih 2 baik” ini dalam skala nasional, dan juga untuk bisa mengantisipasi pengaruh atau guncakan finansial dari luar. UU 3/1999 tentang Bank Indonesia sudah memandatkan sebuah institusi yang melakukan tugas pengawasan sektor jasa keuangan selambat-­‐lambatnya akhir tahun 2002. Pada tahun 2004 undang-­‐undang ini direvisi dan batas waktu pembentukan institusi pengawasan tersebut digeser ke akhir tahun 2010. Rancangan undang-­‐undang OJK akhirnya disetujui oleh DPR Oktober tahun lalu. Otoritas ini akan mengambil alih fungsi pengawasan Bank Indonesia dan Bapepam-­‐LK efektif tahun 2013. Pengawasan tentu dilakukan agar regulasi sektor finansial memang dijalankan dengan disiplin dan akuntabel. Tujuan dari regulasi sektor finansial adalah 1) untuk mempertahankan stabilitas sistemik, 2) mempertahankan keamanan dan keteraturan, dan 3) melindungi konsumen (Llewellyn 1999). Alasan rasional dari regulasi finansial sendiri berfokus pada ketidaksempurnaan pasar dalam sektor keuangan (misalnya eksternalitas, moral hazard atau aji mumpung, dan adverse selection atau salah sasaran). Contohnya, sifat bank sentral sebagai lender of last resort (tumpuan terakhir untuk meminta bantuan pinjaman) sering dapat disalahartikan oleh bank-­‐bank sebagai malaikat yang pasti selalu menolong. Untuk mengatasi kegagalan pasar ini, dibutuhkan regulasi dan pengawasan. Regulasi dapat terbagi menjadi regulasi prudensial dan regulasi atas praktik bisnis. Regulasi prudensial berfokus pada kesehatan para pelaku pasar keuangan, sementara regulasi praktik bisnis lebih melihat ke bagaimana perusahaan keuangan berinteraksi satu sama lain dan dengan konsumen mereka. Dalam hal pengawasan, akan lebih efisien jika badan pengawasnya bersifat tunggal dan independen, karena sistem seperti ini akan memperlancar koordinasi dan dapat memanfaatkan ekonomi skala (economies of scale) dari proses pengawasan (Briault 1999). Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Terlepas dari pentingnya undang-­‐undang OJK, naskahnya masih mengandung ambiguitas (McLeod 2011). Misalnya, Pasal 37 menyebutkan bahwa “OJK dan Bank Indonesia dapat berkoordinasi dan berkerjasama dalam pengawasan bersama atas kegiatan jasa keuangan di bidang perbankan” (Ayat 2). Pasal yang sama juga menyebutkan bahwa “BI dapat melakukan pengawasan langsung dan/atau pengawasan tidak langsung terhadap bank” (Ayat 4). Di sini timbul kesan ketidaktegasan. Seperti dikuatirkan McLeod, ini bisa berarti tidak terjadi transfer fungsi pengawasan dari Bank Indonesia ke OJK – seperti yang diamanatkan oleh UU 3/1999, tapi duplikasi. Ini tentu berpotensi menimbulkan kebingungan atau tumpang-­‐tindih dalam fungsi koordinasi. Pasal ini juga menyebut peran forum stabilitas sistem keuangan. “Forum” ini tidak didefinisikan dalam Ketentuan Umum (Pasal 1). Dengan demikian, kita dapat berasumsi bahwa yang dimaksud dengan forum ini adalah FSSK yang dibentuk tahun 2005 (dan direvisi 2007) berdasarkan keputusan bersama Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Forum ini sendiri dimaksudkan untuk menunjang tugas Komite Koordinasi (“dalam rangka pengambilan keputusan terhadap bank bermasalah yang ditengarai sistemik”), komite yang diketuai Menteri Keuangan, 3 dan beranggotakan Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner LPS. Karena alur koordinasi tidak begitu jelas dalam undang-­‐undang OJK ini, kita berharap peraturan pelaksanaannya akan jauh lebih tegas dan disiplin. Selain penyempurnaan dalam perangkat hukum serta sistem pengawasannya, perlu juga terus mengikuti perkembangan di level global. Kita maklum, OJK dibentuk dengan model FSA (Financial Service Authority) di Inggris. Namun lembaga ini sendiri sedang banyak dikritik karena dianggap tidak mampu melindungi sektor perbankan dan keuangan Inggris dari terjangan GFC. Bahkan FSA sendiri sedang ditinjau lagi untuk penyempurnaan lebih lanjut. Memang saat ini belum ada konsensus tentang bagaimana sebenarnya bentuk ideal dari pengawas keuangan independen. Bahkan untuk pengaturan perbankan di level internasional, penyempurnaan masih terus dilakukan. Basel III pun masih terus diperbaiki. Beberapa ekonom seperti Yoshino dan Hirano (2011) mengusulkan agar persyaratan modal minimum sebaiknya didasarkan pada faktor-­‐faktor ekonomi seperti PDB, pertumbuhan kredit, harga saham, tingkat bunga, dan harga tanah; ukuran ini bisa berbeda-­‐beda antar negara. Dengan kata lain, syarat modal minimum akan bersifat counter-­cyclical: tinggi pada saat perekonomian sedang boom, dan rendah pada saat perekenomian sedang lesu. Hal ini dapat membuat praktik pemberian pinjaman oleh perbankan menjadi lebih stabil. Namun tentu bukan tanpa kesulitan. Akan sulit membangun ukuran yang konsisten dan dapat diperbandingkan antar-­‐negara untuk tujuan pengawasan. Akhirnya, kita berharap agar OJK dapat bekerja dengan efektif. Semoga Indonesia dapat lebih kuat menghadapi tantangan-­‐tantangan di sektor keuangan dan perbankan, baik dari dalam, maupun dari luar negeri. 4