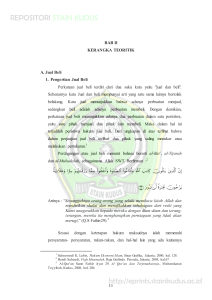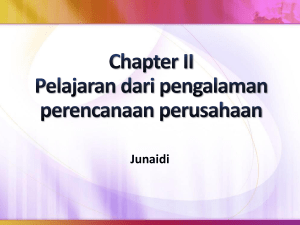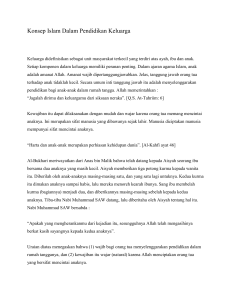ILMU HUDHURI: Konsep Ilmu Pengetahuan
advertisement

UNIVERSITAS INDONESIA ILMU HUDHURI: Konsep Ilmu Pengetahuan dalam Filsafat Iluminasi Suhrawardi TESIS Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Humaniora dalam Bidang Ilmu Pengetahuan Budaya Program Studi Ilmu Filsafat LUQMAN JUNAIDI 0606013292 FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA PROGRAM STUDI MAGISTER HUMANIORA DEPOK JUNI 2009 i Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia. Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima saksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya. Depok, 10 Juli 2009 Luqman Junaidi ii Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar Nama : Luqman Junaidi NPM : 0606013292 Tanda Tangan : Tanggal : 10 Juli 2009 iii Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 HALAMAN PENGESAHAN Tesis ini diajukan oleh Nama : Luqman Junaidi NPM : 0606013292 Program Studi : Ilmu Filsafat Judul Tesis : Ilmu Hudhuri: Konsep Ilmu Pengetahuan dalam Filsafat Iluminasi Suhrawari Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Humaniora pada Program Studi Ilmu Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. DEWAN PENGUJI Pembimbing : Dr. Akhyar Yusuf Lubis (................................) Ketua Penguji : Dr. A. Harsawibawa (................................) Penguji : Vincensius Y. Jolasa, Ph.D (................................) : M. Fuad Abdullah, M.Hum (................................) : Naupal, M.Hum (................................) Ditetapkan di Tanggal : Depok :10 Juli 2009 Oleh Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Prof. Dr. Bambang Wibawarta, MA NIP 19651023199031002 iv Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 KATA PENGANTAR Salah satu kesulitan terbesar dalam mengupas ilmu hudhuri atau epistemologi iluminasi ini adalah, masih adanya rasa skeptis dari sejumlah kalangan tentang keabsahan metodologinya dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Ada anggapan bahwa epistemologi iluminasi lebih dekat ke ranah mistik daripada ke ranah filsafat. Anggapan ini sejatinya cukup beralasan mengingat epistemologi iluminasi dibangun di atas pondasi kecerdasan spiritual, bukan kecerdasan intelektual. Padahal jika ditelusuri lebih jauh, kenyataannya tidaklah demikian. Berbekal penguasaan yang tuntas terhadap pemikiran-pemikiran filsafat yang berkembang sejak Hermes hingga abad pertengahan, Suhrawardi membangun perspektif yang berbeda dalam tradisi kefilsafatan. Dengan ketelitian yang tinggi, dia meramu seluruh teori filsafat yang ada, untuk kemudian mendirikan madzhab baru yang kemudian dikenal dengan nama filsafat ilmuninasi. Konsep yang ia paparkan memang berbeda dengan teori filsafat yang berkembang pada zamannya, khususnya dua aliran besar filsafat Yunani yang dimotori oleh Plato dan Aristoeles. Namun justru di situlah letak originalitas sekaligus keunikan aliran baru yang dibangun oleh Suhrawardi. Faktor inilah yang melatari penulis melakukan penelitian yang mendalam terhadap konsep epistemologi dalam filsafat ilmuniasi. Kendati tujuan awal dari penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar magister dalam bidang filsafat, namun harus diakui bahwa dalam perkembangannya, penulis menyadari terlalu picik jika penelitian yang terasa panjang dan melelahkan ini hanya diperuntukkan bagi tujuan yang terlalu formal. Begitu banyak nilai luhur dalam teori filsafat iluminasi yang belum banyak diketahui oleh masyarakat luas, bahkan oleh kalangan yang meyakini kebenaran ilmu hudhuri karena dilegitimasi oleh ajaran agama. Penulis yakin, seluruh umat Islam—terutama kalangan terdidik—percaya dengan keabsahan ilmu hudhuri, tapi penulis juga yakin, hanya sedikit dari mereka yang mengetahui dengan benar tentang teori, sistematika, serta metodologi epistemologi religius ini. v Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 Karena keyakinan inilah, penulis coba meluhurkan tujuan penulisan tesis ini, dari sekadar memenuhi syarat meraih gelar master, menjadi upaya untuk menghadirkan referensi valid kepada semua orang yang membutuhkan penjelasan ilmiah tentang ilmu hudhuri. Untuk mewujudkan kedua tujuan di atas, penulis terbentur dengan beragam kesulitan teknis dan non teknis. Maklum, saat tesis ini ditulis, kondisi sosial-ekonomi penulis kurang stabil. Perjuangan memburu literatur dengan dana dan waktu yang sangat terbatas, ditambah lagi dengan keharusan memahami karya-karya Suhrawardi yang saangat pelik, sesekali hampir membuat penulis patah arang, tapi Alhamdulillah, berkat pertolongan dan ilham dari Allah Swt., semua kesulitan itu berhasil dilalui. Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan untuk menyelesaikan penulisan tesis ini, terutama: 1. Dr. Akhyar Yusuf Lubis. Di mata penulis, beliau lebih dari sekadar pembimbing penulisan tesis ini. Gayanya yang khas dan periang, membuat seolah hidup ini begitu mudah untuk dijalani. Tak ada beban yang perlu dikhawatirkan, karena semuanya bisa mengalir dan dituntaskan. Tinggal keseriusan kita dalam menjalaninya. Kendati penulis tidak banyak berinteraksi dengan beliau selama penulisan tesis ini, namun masukan yang beliau berikan, sungguh-sungguh mampu memecah kebuntuan yang kadang penulis rasakan. 2. Vincenssius Y. Jolasa Ph.D. Secara jujur penulis merasa berutang budi besar kepada beliau. Dengan tutur kata yang santun, beliau tak pernah bosan mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan proses penulisan tesis ini, supaya penulis bisa segera melangkah pada episode hidup yang selanjutnya. Dorongan, nasihat, serta kesediaan berbagi pengalaman semasa menjadi mahasiswa, benar-benar membangkitkan motivasi penulis bahwa tak ada karya yang mungkin untuk diselesaikan, selama kita serius menggarapnya. 3. Dr. A. Harsawibawa. Sebagai Ketua Tim Penguji tesis ini, penulis ingin menyampaikan rasa salut kepada cara beliau dalam memimpin jalannya vi Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 ujian. Tidak mendominasi jalannya ujian, serta memberikan kesempatan yang luas kepada penguji lain untuk membedah tesis ini, bagi penulis merupakan bukti sahih betapa Pak Harsa—demikian kami memanggilnya, sangat jauh dari kesan arogan. Senyum khasnya membuat penulis tidak mearasa tegang selama proses ujian berlangsung. 4. M. Fuad Abdullah M.Hum. Penguasaan terhadap bahasa Arab dan filsafat Islam yang begitu dalam, membuat Pak Fuad—sapaan akrabnya, sangat detail dalam membedah tesis ini. Beliaulah yang mengafirmasi semua kutipan teks Arab dalam tesis ini. Berkat koreksi beliaulah, kesalahan teknis pada penulisan kutipan Arab dalam tesis ini bisa dieliminir. 5. Naupal M.Hum. Harus penulis akui bahwa ternyata di balik sosoknya yang santai, Pak Naupal begitu menguasai esesnsi tesis ini. Pertanyaanpertanyaan beliau sangat mendalam dan sangat menyentuh inti dari persoalan yang penulis ketengahkan. Bagi penulis, Pak Naupal adalah representasi dari adagium “Serius tapi santai”. 6. Ayahanda Junaidi Zainal Abidin dan Ibunda Maftuhah, yang tak pernah lelah memotivasi penulis untuk terus berkarya. Dukungan moril dan doa yang dipanjatkan oleh keduanya, penulis yakini sebagai salah satu pilar utama yang menyukseskan penulis menempuh studi magister di Universitas Indonesia. Kemudian juga adinda Ghufron Junaidi. Ia memang masih belum tahu banyak tentang dunia perkuliahan waktu penulis menggarap tesis ini, karena masih duduk di bangku aliyah. Namun siapa sangka bahwa dari diskusi ringan yang kami bangun berdua, ternyata memantik cita-citanya untuk mengikuti jejak penulis, mengambil kuliah filsafat. 7. Anak dan istriku tercinta, Muslichatin dan Akbar Afkariz Zaman. Tawa dan canda meraka ibarat oase yang menyegarkan semangat penulis, menghibur saat kejenuhan melanda, serta sumber kedamaian yang membuat penulis selalu merasakan ketenangan dan ketentraman. Penulis juga tak lupa untuk menyampaikan terima kasih kepada semua dosen, kerabat, serta sahabat seperti Bapak Ignatius Susilo, Yulius Aris Widiantoro, Eric Tiwa, serta Arif yang telah banyak membantu penyelesaian studi vii Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 magister ini. Sedikit pun penulis tidak akan pernah lupa terhadap semua kenangan indah yang kita lalui semasa belajar filsafat bersama di bangku S2 UI. Mbak Munawaroh yang selalu bersedia dimintai bantuan di sela-sela kesibukannya sebagai staf administrasi di Departemen Ilmu Filsafat, dan masih banyak lagi yang lain. Kendati tidak penulis sebutkan satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat sekaligus terima kasih yang tak terhingga dari lubuh hati yang paling dalam. Besarnya jasa, dukungan, serta bantuan yang mereka berikan, sungguh mustahil penulis balas dengan sempurna. Semoga Allah Swt. mencatat amal kebaikan kalian semua sebagai amal salih, dan mendapat balasan yang berlipat ganda, baik di dunia maupun di akhirat. Jakarta, 10 Juni 2009 Luqman Junaidi viii Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Luqman Junaidi NPM : 0606013292 Program Studi : Ilmu Filsafat Departemen : Filsafat Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya Jenis karya : Tesis Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: ILMU HUDHURI: Konsep Ilmu Pengetahuan dalam Filsafat Iluminasi Suhrawardi Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Dibuat di : Depok Pada tanggal : 10 Juli 2009 Yang menyatakan : Luqman Junaidi ix Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 ABSTRAK Nama : Luqman Junaidi Program Studi : Ilmu Filsafat Judul : Ilmu Hudhuri: Konsep Ilmu Pengetahuan dalam Filsafat Iluminasi Suhrawardi Dalam ranah epistemologi, iluminasionisme memang tidak sepopuler empirisme dan rasionalisme. Banyak kalangan yang skeptis, menganggap metode memperoleh ilmu pengetahuan yang bertumpu pada kekuatan hati dan perasaan ini sebagai luapan pengalaman spiritual-mistis yang sangat personal, dan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Anggapan ini sejatinya lahir dari kecenderungan para iluminasionis yang menulis karya mereka dalam bahasa yang sulit dimengerti, sarat dengan kiasan, dan terkadang abai pada argumentasi logis dan analisa yang ketat. Di tangan Suhrawardi, benang kusut epistemologi iluminasi ini terurai sempurna. Dengan bahasa yang lugas dan argumentasi yang logis, ia mampu menyajikan sistematika ilmu hudhuri atau ilmu yang diperoleh melalui metode iluminasi sehingga benar-benar membumi dan sangat terbuka untuk diafirmasi. Tesisi ini mengupas tuntas keberhasilan Suhrawardi dalam membuktikan keunggulan epistemologi iluminasi atas epistemologi yang lain. Suatu epistemologi yang efektif dalam mentransformasi pengetahuan intuitif serta pengalaman mistik ke dalam kemampuan berpikir yang konsisten dan koheren. Kata kunci: Epistemologi, Filsafat Iluminasi, Ilmu Hudhuri, Teori Cahaya, Pengetahuan diri x Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 ABSTRACT Name Study Program Title : Luqman Junaidi : Science Philosophy : Hudhuri Science : Concepts in Philosophy of Illumination Science Suhrawardi In the realm of epistemology, illuminationism is not as popular as empiricism and rationalism. Many people are skeptical, consider the method of acquiring knowledge based on the strength of the heart and this feeling as a surge of spiritual - mystical experience that is highly personal, and cannot be proven scientifically. This assumption is actually born from the tendency of the illuminationist who wrote their works in a language that is difficult to understand, full of allusion, and sometimes neglect the logical arguments and rigorous analysis. In the hands of Suhrawardi, the tangled threads epistemology illumination is perfectly unraveled. With simple language and logical argument, he was able to present a systematic hudhuri science or knowledge obtained through the method of illumination so it's really down to earth and very open to be affirmed. This Thesis discuss thoroughly Suhrawardi’s triumph in proving the superiority of illumination epistemology over the other epistemologies. An epistemology that is effective in transforming mystical intuitive knowledge and experience into consistent and coherent thinking skills. Keywords: Epistemology, Philosophy of Illumination , Hudhuri Science , Theory of Light , Self Knowledge xi Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS HALAMAN PENGESAHAN KATA PENGANTAR HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ABSTRAK DAFTAR ISI i ii iii iv v ix x xii BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tinjauan Pustaka 1.4 Tujuan Penelitian 1.5 Manfaat Penelitian 1.6 Metode Penelitian 1.7 Sistematika Penulisan 1 1 7 9 10 11 12 15 BAB 2 BIOGRAFI SINGKAT SUHRAWARDI 2.1 Latar Belakang Sosio-Historis 2.2 Hasil Kreativitas Intelektual 2.3 Atmosfer Keilmuan Pada Masa Suhrawardi 2.4 Pengaruh Suhrawardi Pada Perkembangan Pemikiran Islam 17 17 25 28 36 BAB 3 LANDASAN PRAEPISTEMIK ILUMINASI 3.1 Selayang Pandang Filsafat Iluminasi 3.2 Lingkup Bahasan Filsafat Iluminasi 3.2.1 Kosmologi 3.2.2 Psikologi 3.2.3 Epistemologi 3.3 Klasifikasi Ilmu 3.4 Landasan Historis Ilmu Hudhuri EPISTEMOLOGI 45 45 48 50 53 57 60 69 BAB 4 DIMENSI EMPIRIS EPISTEMOLOGI ILUMINASI 4.1 Teori Definsi 4.2 Teori Penyaksian 4.3 Teori Objek 75 75 82 87 BAB 5 DIMENSI INTUITIF EPISTEMOLOGI ILUMINASI 5.1 Teori Cahaya 5.2 Pengetahuan Diri 5.3 Tahapan Memperoleh Ilmu Hudhuri 90 90 96 105 xii Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 BAB 6 PENUTUP 6.1 Kesimpulan 6.2 Studi Kritis Atas Konsep Epistemologi Suhrawardi 6.3 Posisi Epistemologi Suhrawardi 6.4 Rekomendasi untuk Kajian Lebih Lanjut 113 113 115 118 122 DAFTAR PUSTAKA 128 xiii Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Saat menjejakkan kaki dalam ranah filsafat Islam dan coba memfokuskan kajian pada tokoh yang bernama Suhrawardi, setidaknya ada dua ironi besar yang segera membentang dan menarik untuk dicermati. Pertama, jika dibandingkan dengan para filsuf Muslim yang lain, nama Suhrawardi jelas kurang populer di Indonesia. Tidak banyak peminat studi filsafat yang mengenalnya, apalagi mengupas pikiran-pikirannya. Dalam katalog para pemikir besar Islam yang dianggap sebagai inspirator kemajuan peradaban, namanya—meminjam istilah Suhrawardi sendiri—bagaikan nur al-'aridh (cahaya temaram) yang kalah gemerlap dari Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, al-Farabi, atau bahkan al-Kindi. Oleh sebab itulah, para pengkaji yang tertarik untuk mendalami teori filsafatnya, harus menata mental-akademis semapan mungkin karena akan berhadapan dengan kenyataan pahit minimnya referensi sekunder yang bisa diakses. Bagi sebagian kalangan, mungkin akan segera terbuncah pernyataan: "Mengapa tidak merujuk langsung ke sumber primer? Bukankah hanya dengan begitu hasil penelitian yang lebih valid, akurat, autentik, dan original didapatkan?" Benar. Namun masalahnya adalah, Suhrawardi berbeda dengan para filsuf Islam kebanyakan. Dalam menuangkan gagasan-gagasannya, ia tidak menggunakan bahasa konvensional yang mudah dipahami. Akan tetapi ia mengemas karyanya dalam bahasa simbolik yang sarat mistik sehingga sangat sulit dimengerti. Metode seperti ini, menurut Komaruddin Hidayat, disebabkan oleh ketidakmampuan narasi deskriptif untuk menjelaskan dan menghadirkan pengalaman unik, realitas absolut, intuisi, dan imajinasi yang datang tiba-tiba. (Hidayat, 1996, 83) Indikasi inilah yang mungkin menjadi salah satu faktor mengapa studi terhadap pemikiran Suhrawardi, jauh lebih sedikit dibanding dengan studi terhadap para filsuf Islam yang lain. Tingkat kerumitan yang luar biasa untuk memahami karya-karyanya itulah, yang mungkin membuat para peminat studi filsafat Islam merasa enggan untuk melakukan penelitian yang intensif terhadap Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 2 gagasan Suhrawardi, dan lebih memilih untuk mengupas salah satu aspek pemikiran tokoh lain. Sirajuddin Zar misalnya, guru besar filsafat Islam IAIN Imam Bonjol Padang ini dalam karyanya yang berjudul Filsafat Islam, menghentikan uraiannya pada Ibnu Rusyd—yang hidup hanya beberapa tahun sebelum Suhrawardi. MM Syarif juga demikian, dalam suntingannya yang berjudul A History of Muslim Philosophy (edisi Indonesia: Para Filsuf Muslim), ia melewatkan kajian tentang Suhrawardi, padahal, pemikir yang hidup setelahnya, Nashiruddin al-Thusi ia paparkan secara lincah dan mendetil. Untuk mengatasi pelbagai kesulitan terminologis dalam memahami karyakarya Suhrawardi, ada baiknya jika para peminat kajian filsafat iluminasi melirik sumber-sumber sekunder, baik yang ditulis oleh komentator sang filsuf semisal Syarh Hikmah al-Isyraq karya Syamsuddin Muhammad al-Syahrazuri, atau Syarh Hikmah al-Isyraq yang dirilis oleh Quthbuddin al-Syirazi, atau pun karya-karya lain yang mengupas teori filsafatnya. Dengan begini, secercah cahaya kemudahan akan terpancar dan bisa digunakan sebagai panduan untuk mengarungi samudera pemikiran Suhrawardi yang sangat luas dan mendalam. Anehnya—dan di sinilah letak ironi yang pertama, meskipun nama Suhrawardi kurang begitu dikenal dalam semarak kajian filsafat Islam, bahkan seakan terpinggirkan, (Drajat, 2005, 56) teorinya sangat monumental, idenya diakui sebagai gagasan yang brilian, bahkan karyanya yang berjudul Hikmah alIsyraq dinilai sebagai karya agung yang telah memberikan sumbangan signifikan bagi khazanah intelektual Islam (Kartanegara, 2002, 64). Penilaian seperti ini sejatinya sangat wajar jika dibandingkan dengan besarnya pengaruh yang ditorehkan Suhrawardi bagi peta pemikiran Islam setelahnya. Sebagai misal, metode intuitif—yang bersumber pada hati—dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang ia gagas, tetap lestari, menjadi topik yang menarik untuk dikaji, sekaligus memberikan tawaran alternatif dalam upaya memperoleh ilmu pengetahuan sejati, di samping 2 metode yang telah populer sebelumnya; [1] Metode observasi yang bersumber pada indra, [2] metode demonstratif yang mengandalkan kekuatan akal. Kesan yang ditinggalkan Suhrawardi sangat dalam bagi para pemikir setelahnya. Hal ini terbukti dengan tampilnya sejumlah pemikir yang, disadari Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 3 atau tidak, sangat terpengaruh dengan ajaran-ajaran tokoh yang ditasbihkan sebagai pendiri madzhab iluminasi ini. Contohnya adalah Nashiruddin al-Tushi dan Mulla Shadra.(Drajat, 2001, 89). Di tangan tokoh yang tersebut terakhir inilah, bias filsafat ilmuninasi terpancar luas dan mendapat posisi terhormat di antara sekian banyak teori filsafat Islam yang lain. Menurut Seyyed Hosein Nasr, Mulla Shadra memperoleh pengajaran filsafat iluminasi dari gurunya yang bernama Mir Damad, seorang filsuf, mistikus, teolog, dan pujangga yang juga dikenal sebagai pendiri Madzhab Isfahan. Mir Damad adalah figur yang secara benar mengajar filsafat Ibnu Sina yang ia artikulasi ke dalam sistem filsafat ilmuninasi. Jadi, melalui Mir Damad ini, pengaruh Suhrawardi secara sempurna dapat ditransfer ke Mulla Shadra. Melihat besarnya pengaruh Suhrawardi dalam Shadra, Nasr tidak ragu untuk mengatakannya sebagai sosok yang benar-benar mewakili kesempurnaan norma Suhrawardian (Nasr, 1996, 77). Kedua, intuisi, visi, ilham—dan beragam istilah lain yang searti, merupakan terminologi unik yang menghiasi sejarah panjang kreativitas manusia dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Metode ini tidak hanya subur dalam tradisi Islam, tapi juga berkembang dalam hampir—kalau tidak mau dikatakan seluruhnya—semua agama, serta ranah kefilsafatan, dari klasik hingga modern. Di Barat misalnya, sempat muncul aliran intuisionisme yang memiliki pengaruh luar biasa. Aliran yang dipopulerkan Henry Bergson ini mempertentangkan pengetahuan rasional dengan persepsi langsung terhadap kenyataan yang dilandasi intuisi. Intuisi dimengerti sebagai kemampuan khusus pikiran, yang tidak dapat dijabarkan pada pengalaman indrawi dan pikiran diskursif. Pada titik ini, intuisionisme sangat dekat dengan mistisisme. (Bagus, 2002, 368). Selain Bergson, Fichte juga bisa digolongkan sebagai tokoh yang menghargai intuisi. Menurutnya, pengetahuan intuitif (scientia intuitiva) adalah pengetahuan yang paling sempurna, mengatasi pengetahuan indra (empiri) dan akal budi (rasio). Alasannya, pengetahuan ini memberi kemampuan untuk melihat sesuatu dalam perspektif keabadian (Akhyar, 2004, 203). Dalam Islam, epistemologi intuitif ini mendapatkan kedudukan sakral sekaligus mulia karena mendapatkan legitimasi tegas dalam al-Quran. (QS 18: Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 4 65). Oleh sebab itulah, tidak berlebihan kiranya jika banyak filsuf dan mistikus Islam yang mendaulat intuisi sebagai epistemologi yang paling tinggi! Ibnu Arabi misalnya, ia tidak ragu untuk menjadikan intuisi sebagai poros sekaligus intisari dari seluruh filsafat mistisnya. (Afifi, 1995,148) Bahkan, pemikir besar yang paling populer di kalangan umat Islam, Imam al-Ghazali, rela menyediakan bab khusus dalam karya monumentalnya yang berjudul Ihya' Ulumuddin untuk mengulas ilmu yang ia sebut sebagai ilmu Mukasyafah ini. . أﻣﺎ اﻷوﻟﯿﺎء ﻓﯿﺄﺧﺬون ﻋﻦ اﷲ. ﻓﯿﺒﻌﺪ اﻟﻨﺴﺐ،اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ “Ulama syariat mengambil ilmu mereka dari generasi terdahulu sampai Hari Kiamat. Semakin hari ilmu mereka semakin jauh dari sumbernya. Para wali mengambil ilmu mereka langsung dari Allah.” (Ibnu Arabi dalam Muhammad Jamil Ghazi, 35) و ، ﻓﺈن ﻛﺎن ﻋﻠﻤﮫ ﻣﺴﺘﻔﺎدا ﻣﻦ ﻧﻘﻞ أوﺷﯿﺦ.ﺑﻼ واﺳﻄﺔ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ وﺷﯿﺦ .ﻋﻦ اﻷﺧﺬ ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺪﺛﺎت Bagi kami, kedudukan seseorang dalam ranah ilmu pengetahuan belum sempurna hingga ia memperoleh ilmunya dari Allah Azza wa Jalla tanpa perantara tulisan atau guru. Apabila ia memperoleh ilmunya dari tulisan atau guru, berarti ia mendapatkan ilmunya dari entitas yang baharu. (Ibnu Arabi dalam al-Sinqithi, 229) Karena mendapatkan justifikasi dari al-Quran dan Hadis, sudah barang tentu ilmu yang diperoleh dari intuisi ini menjadi kebenaran yang langsung diterima dan tidak dipertanyakan lagi. Walaupun dalam sejumlah kasus pengetahuan yang diperoleh melalui cara ini sulit diterima akal sehat, atau terkesan tidak selaras dengan teks-teks suci—seperti ketika Ibnu Arabi menggagas teori wihdatul wujud atau saat Abu Yazid al-Bisthami mengemukakan teori hulul, tetap saja banyak yang menerimanya secara simultan. Mengapa? Sekali lagi, karena ilmu pengetahuan itu diyakini bersumber langsung dari Zat Yang Mahatahu. Titik persamaan corak ilmu pengetahuan semacam ini, baik di Barat maupun di Timur adalah, para tokohnya seakan tidak mampu menyajikan uraian pemikiran mereka secara bernas dan lugas. Contohnya Bergson, banyak yang mengakui gaya bahasanya bagus. Uraiannya menjadi lebih hidup dan menarik karena dihiasi pelbagai kiasan, perbandingan, dan contoh. Namun gaya penulisan yang berbau sastra ini memiliki sisi negatif. Menurut Bertens, Bergson kerap kali Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 5 mengabaikan argumentasi logis yang ketat, dan analisa yang sabar dan teliti. Akibatnya, banyak kritisi yang menganggapnya lebih sebagai seorang penyair atau mistikus daripada seorang filsuf yang serius. (Bertens, 2001,12). Fenomena yang sama juga terjadi dalam dunia Islam, banyak orang yang lebih memosisikan al-Ghazali, Ibnu Arabi, dan Abu Yazid al-Bisthami sebagai seorang mistikus dibanding seorang filsuf. Malah dalam skala yang lebih luas, banyak orang yang kesulitan untuk menentukan posisi pasti seorang pemikir; apakah dia filsuf atau mistikus. Pasalnya, menurut laporan sejarah, hampir semua filsuf Islam menjalani hidup mereka secara asketis seperti seorang mistikus. Dan, pola hidup semacam ini diyakini sebagai salah satu tangga dalam perjalanan mendaki menuju pucak kedekatan dengan Tuhan, untuk kemudian mendapatkan pancaran cahaya dalam bentuk ilmu pengetahuan hakiki. Di sinilah letak persoalan sekaligus pangkal ironi yang kedua. Semua kalangan akademisi Muslim memercayai kebenaran dan keabsahan ilmu yang diperoleh melalui jalan intuisi. Sayangnya, mereka seakan tidak pernah bisa menguraikan ilmu itu secara sistematis, runtut, dan mudah dipahami. Gaya penulisan seperti ini pada kenyataannya telah menjerat para peneliti yang berminat mendalami pemikiran mereka dengan jaring-jaring kesulitan yang, seharusnya tidak perlu terjadi. Para peneliti tersebut seakan dipaksa mengarungi lorong panjang nan berliku untuk mencapai tujuan yang sebenarnya tidak jauh. Bagi orang-orang yang kurang sabar, besarnya kompleksitas untuk memahami naskah-naskah berkualitas tapi sulit dimengerti tersebut, bisa mengantarkan pada kesimpulan yang salah. Akhirnya, lahirlah beragam tuduhan miring terhadap para pemikir Islam, seperti kafir, murtad, dan lain sebagainya. Sebagai sosok yang merasakan pahitnya buah tuduhan miring ini sehingga harus mengakhiri hidup di tiang gantungan, Suhrawardi secara ajaib telah meninggalkan karya yang bisa dijadikan landasan indah nan elegan untuk mengurai benang kusut epistemologi intuitif. Gagasan-gagasan yang ia hamparkan membuat ilmu yang diperoleh secara intuitif seolah membumi dan terbuka untuk diafirmasi. Dengan demikian, tingkat keabsahan yang diperoleh dari ilmu semacam ini bisa disejajarkan dengan ilmu yang diperoleh melalui metode observasi atau demonstrasi. Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 6 Dengan meretas jalan yang dibentangkan Suhrawardi, para filsuf tidak perlu ragu lagi untuk menuangkan ilmu pengetahuan yang mereka peroleh melalui ilham dalam karya yang jelas dan gamblang. Di samping itu, para pakar eksoteriempiris yang umumnya hanya membenarkan ilmu yang diperoleh melalui observasi dan demontrasi, tidak memiliki celah untuk memungkiri kebenaran yang dihasilkan dari ilmu yang diperoleh melalui intuisi. Konsekuensinya, mereka juga tidak lagi mempunyai dasar yang kuat untuk melemparkan pelbagai tuduhan murahan kepada para pakar esoteris. Pada tataran ini, Suhrawardi secara tidak langsung sejatinya telah memberikan solusi aplikatif yang dapat menyelesaikan pertikaian abadi antara para eksoteris yang diwakili oleh ahli-ahli fiqih dan teolog dan ahli esoteris yang diwakili oleh kaum sufi dan mistikus. Di samping kedua ironi di atas, faktor lain yang membuat penulis semakin terpicu dan terpacu mengangkat tema ini adalah, adanya ketimpangan dalam dunia intelektualitas Islam. Ketimpangan ini terlihat jika kita mengamati kekayaan khazanah pemikiran Islam yang sangat luar bisa, kemudian membandingkan dengan lesunya kajian tentang filsafat dan mistisisme dalam Islam.. Apabila ditinjau dari segi banyaknya warisan yang ditinggalkan, saya yakin para cendekiawan Muslim klasik adalah sosok paling produktif dibanding para cendekiawan dari belahan dunia mana pun dan dalam kurun waktu kapan pun! Pernyataan ini tidak bombastis dan tidak dilandasi oleh faktor subjektifitasreligius, namun dilandaskan pada fakta sejarah. Coba bayangkan, al-Kindi selama hidupnya bisa menulis 270 risalah, al-Razi mampu menulis 118 buku, al-Farabi 70 buku. Yang sangat menakjubkan adalah mistikus terbesar Islam Ibnu Arabi. Menurut sumber yang dikutip William C. Chittick, tokoh yang digelari Syaikh Akbar (Guru Besar) ini menulis 700 buku, risalah, dan kumpulan puisi yang berjumlah lebih dari 400 buah! (Chittick, 2001, 6). Dilihat dari banyaknya tulisan yang dihasilkan, jangan buru-buru bersikap pesimistik dengan mengira bahwa karya itu tak lebih dari buku tipis yang tak berkualitas, apalagi kalau dibandingkan dengan kemampuan serta waktu yang dibutuhkan cendekiawan modern dalam menulis buku. Sekadar perbandingan, master pies Ibnu Arabi yang berjudul Futuhat al-Makkiyah dalam edisi Osman Yahya terdiri dari 1700 halaman! Coba bandingkan dengan Tractatus Logico- Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 7 Phylosophicus, karya yang sudah dipandang cukup untuk menyebut Ludwig Wittgenstein sebagai salah satu filsuf besar ini hanya berjumlah 75 halaman (Bertens, 2002, 44). Padahal selain Tractatus, Wittgenstin hanya memublikasikan Philoshophsche Untersuchungen, sementara selebihnya adalah teks-teks catatan pribadi atau persiapan untuk kuliah. (Bertens, 2002, 43) Salah satu penyebab mengapa warisan kearifan, kebijaksanaan, intuisi, visi, dan nilai-nilai luhur ini lebih setia menghiasi lemari-lemari perpustakaan daripada mengisi kajian dan studi-studi ilmiah adalah karena tidak diolah dengan kecakapan metodologis yang memadai. Banyak sarjana Muslim klasik yang sudah merasa puas dengan intuisi dan kesadaran, sehingga mengabaikan logos dan nalar. Padahal, intuisi tanpa logos ibarat cahaya tanpa medium yang dapat memancarkan sinarnya. Ia hanya terang pada dan menerangi diri sendiri, sedangkan di sekitarnya tetap gelap gulita. Dan, rasa tanpa nalar laksana api tanpa obor yang dapat membatasi volumenya. Ia bisa berkobar dan membesar lalu menghanguskan semua yang ada di sekelilingnya. Kongkritnya, banyak ilmuwan Muslim yang berkat kebeningan kalbu serta refleksi filosofisnya yang mendalam, mampu meraih kebenaran atau menyingkap makna di balik realita. Sayangnya, mereka tidak bisa memberikan penjelasan yang logis dan rasional dengan metode penalaran yang runtut dan sistematis. Akibatnya, pengetahuan yang mereka dapatkan hanya mencerdaskan diri mereka sendiri, sedangkan gelora rasa yang meletup-letup dalam dada hanya mengantarkan mereka pada ekstase spiritual yang bisa dinikmati sendiri. Kenyataan inilah yang membuat penulis merasa tertarik untuk menyajikan epistemologi iluminasi. Suatu epistemologi yang efektif dalam mentransformasi pengetahuan intuitif serta pengalaman mistik ke dalam kemampuan berpikir yang konsisten dan koheren. 1.2. Rumusan Masalah Secara sederhana penulis telah menguraikan pembagian 3 metode dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Yaitu, metode observasi, metode demonstrasi, dan metode intuisi. Ketiga metode ini tentunya memiliki metodologi dan epistemologi yang berbeda satu sama lain. Untuk membedakan antara metode observasi dengan Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 8 metode demontrasi bukanlah pekerjaan sulit mengingat basis penelitian dalam kedua metode itu berbeda secara tegas. Yang pertama berbasis pada indra, sedangkan yang kedua berbasis pada rasio. Yang sulit adalah bagaimana membedakan antara metode demonstrasi dengan metode intuisi, mengingat basis keduanya sama-sama unsur yang ada dalam diri manusia. Dengan kata lain, bagaimana membedakan akal sebagai basis demonstrasi dengan hati selaku basis intuisi? Masalah ini harus dirumuskan secara jernih agar kita memiliki kesamaan persepsi dan pandangan dalam mengulas kajian ini. Perbedaan ini sebenarnya bermuara pada ketidaksamaan filsafat Islam dengan filsafat Barat dalam mendefinisikan manusia. Sejak istilah animal rationale dipopulerkan filsuf Yunani klasik, pemikir Barat modern seolah terkunci dalam sebuah reduksi sederhana dengan memetakan manusia sebagai makhluk yang tersusun dari dua substansi, jiwa dan raga. Diskusi-diskusi selanjutnya hanya berkutat pada faktor mana yang lebih dominan dalam diri manusia. Para filsuf yang memenangkan dominasi raga atas jiwa lazim disebut sebagai materialisme. Menurut mereka, manusia semata-mata terdiri dari materi, jiwa atau roh itu tidak ada, kalau pun ada tak lebih dari sifat dari materi. Sementara para filsuf yang mengunggulkan dominasi jiwa atas raga biasa disebut immaterialisme, spiritualisme, atau idealisme. Mereka meyakini bahwa manusia semata-mata bersifat rohani, sedangkan materi itu tidak ada, kalau pun ada tak lebih dari sifat dari jiwa atau roh. (Van Peursen, 1988, 120). Ketika filsafat Barat masih berkutat dengan dua dimensi manusia ini, filsafat Islam sudah selangkah lebih maju dengan mengatakan bahwa manusia adalah makhluk multi dimensi yang tidak hanya terbentuk dari dua substansi. Makanya, mayoritas filsuf Muslim menolak definisi manusia sebagai hewan yang berakal. Alasan mereka, definisi semacam ini menafikan keberadaan dimensi ketiga yang justru merupakan dimensi paling substantif nan esesnsial. Yaitu hati, atau kalbu, atau nurani. Mereka tidak setuju penyamaan akal dengan hati apalagi penggolongannya menjadi satu; dimensi rohani manusia. Sebab, secara faktual, keduanya memang memiliki cara kerja yang berbeda. Untuk memudahkan, silakan simak ilustrasi alGhazali berikut. Jika manusia diibaratkan sebuah kerajaan, maka hati adalah raja, Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 9 akal adalah menteri, sementara anggota tubuh adalah rakyat yang selalu patuh. Raja pasti menginginkan kerajaannya utuh dan makmur sehingga seluruh usahanya pasti diarahkan untuk mewujudkan keinginan itu, akan tetapi tidak demikian dengan menteri, karena didorong motif-motif tertentu, adakalanya mereka bersikap culas sehingga membahayakan kerajaan. Berdasarkan steksa sederhana ini bisa disimpulkan, dalam Islam ada 3 model epistemologi yang bisa digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Pertama, epistemologi observatif yang model penelitiannya menggunakan pengamatan indrawi. Kedua, epistemologi demonstratif yang model penelitiannya memakai analisa-analisa logis. Ketiga, epistemologi iluminatif yang model penelitiannya mengandalkan kekuatan hati saat berinteraksi langsung dengan objek yang hadir dalam kesadaran. Objek kajian dalam karya ilmiah ini adalah model epistemologi yang ketiga. Mengingat banyaknya tokoh yang mengulas epistemologi model ini, tentu dibutuhkan studi yang luas. Namun hal itu pasti memerlukan waktu yang relatif lama dan tingkat kesulitan yang tinggi. Oleh sebab itu, penulis memutuskan untuk memfokuskan penelitian ini pada pemikiran seorang tokoh saja, yaitu Suhrawardi. Jadi, kalau dirumuskan dalam ungkapan yang singkat, maka tesis stemenet untuk kajian ini adalah, Konsep Epistemologi dalam Filsafat Iluminasi Suhrawardi. 1.3. Tinjauan Pustaka Sebelum menulis karya ilmiah ini, penulis telah melakukan tinjauan pustaka terhadap karya-karya ilmiah yang membahas masalah pemikiran Suhrawardi, dan sejauh penelusuran penulis di perpustakaan UI dan UIN Syarif Hidayatullah, hanya ada 2 skripsi, 1 tesis, dan 2 disertasi tentang Suhrawardi. Uniknya, semua karya itu ditulis oleh mahasiswa-mahasiswa UIN. Dengan kata lain, sampai saat ini, tak satu pun mahasiswa UI yang kelihatannya tertarik untuk menulis tentang tokoh ini. Skripsi pertama yang mengupas pemikiran Suhrawardi ditulis oleh Masyhar pada tahun 2002 dengan judul Kritik Suhrawardi al-Maqtul Terhadap Logika Peripatetik. Dalam karya ilmiah ini, Masyhar membahas 3 kritik Suhrawardi terhadap logika Peripatetik. [1] pembuatan definisi, [2] masalah Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 10 konversi, [3] silogisme. Sementara skripsi kedua ditulis oleh penulis sendiri pada tahun 2005 dengan judul Kosmologi di Mata Sang Iluminasionis. Dalam karya ini, penulis memaparkan proses penciptaan alam semesta melalui cara iluminasi. Kajian yang lebih komprehensif terhadap pemikiran Suhrawardi dapat ditemui melalui karya ilmiah yang ditulis oleh Amroeni Drajat. Tesis yang ditulis untuk meraih gelar master di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini berjudul Falsafah Iluminasi: Sebuah Kajian Terhadap Konsep Cahaya Suhrawardi. Karya ilmiah ini mengupas secara tuntas konsep cahaya yang terdapat dalam filsafat iluminasi. Seperti proses penyebaran secara vertikal, horizontal, serta masalahmasalah lain yang terkait dengan masalah cahaya ini. Seakan ingin menyempurnakan penelitiannya mengenai pemikiran Suhrawardi, ketika hendak menyelesaikan program S3 di Institut yang sama, Amroeni Drajat kembali menulis mengenai pemikiran Suhrawardi. Akan tetapi, kali ini yang ia tekankan adalah ktirik Suhrawardi terhadap filsafat peripatetik. Lengkapnya, disertasi tersebut berjudul Kritik Terhadap Falsafah Peripatetik: Analisis Pemikiran Hikmah al-Isyraq. Jika dilihat dari judulnya, disertasi ini terkesan memiliki kesamaan dengan skripsi yang ditulis Masyhar. Sayangnya, kesan itu akan hilang begitu kita membaca kedua karya tersebut secara lengkap. Disertasi yang kedua adalah karya Asmuni yang ditulis pada tahun 2008 dengan judul Kesatuan Mistik dalam Filsafat Iluminasi (Isyraqi) Suhrawardi. dalam karya ini Asmuni menegaskan bahwa ada dua interpretasi yang dapat diajukan berkaitan dengan konsep kesatuan mistik ini. Pertama, kesatuan dengan keindentikan diri atau swa-identitas. Berdasarkan konsep ini maka kesatuan mistis dipahami sebagai kesatuan sempurna dengan Tuhan melalui ilmu hudhuri. Kedua, kesatuan mistis dalam arti pencerahan dan penyerapan. Artinya, diri sebagai emanasi Tuhan adalah kesatuan kehadiran Tuhan di dalam manusia, sekaligus kehadiran manusia di dalam Tuhan. Selain karya-karya yang dipaparkan di atas, tidak menutup kemungkinan masih ada karya ilmiah lain tentang Suhrawardi yang luput dari perhatian penulis. Hal ini didasari fakta bahwa institusi pendidikan yang membuka kajian filsafat bukan hanya UI dan UIN Syarif Hidayatullah semata. Akan tetapi masih banyak institusi pendidikan lain yang menyelengarakan kajian tersebut. Namun karena Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 11 terbatasnya waktu, penulis hanya memfokuskan penelusuran pada dua perpustakaan di dua institusi pendidikan besar tersebut. 1.4. Tujuan Penelitian Secara umum, tujuan penulisan tesis ini adalah: 1. Memperkenalkan suatu konsep epistemologi unik yang, walaupun tidak baru dan aktual, nampaknya kurang diminati oleh kalangan akademisi, sehingga dalam ranah intelektualitas, epistemologi ini seolah termarginalkan. 2. Memperoleh pemahaman yang utuh dan menyeluruh tentang konsep ilmu pengetahuan dalam madzhab iluminasi Suhrawardi. 3. Memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar master di bidang kajian ilmu filsafat. 1.5. Manfaat Penelitian Berangkat dari tujuan yang melatari penulisan karya ilmiah ini, setidaknya ada sejumlah manfaat yang bisa dipetik darinya; seperti: 1. Menginsyafkan kalangan akademisi bahwa ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui jalan intuisi adalah benar, absah, bisa dipertanggungjawabkan, serta bisa dituangkan dan diterangkan dengan metodologi yang ketat dan rigorus. 2. Membentangkan jalan bagi para mistikus serta filsuf yang menghargai intuisi agar mereka bisa menjelaskan ilmu pengetahuan yang mereka miliki dengan bernas, lugas, dan cerdas. Walaupun tidak berlaku universal, akan tetapi selama ini kita dapati mayoritas mistikus dan filsuf beraliran intuisionisme mengalami kesulitan untuk menguraikan sistematika pemikiran mereka secara gamblang. Banyak mistikus Muslim yang terjebak dalam pelbagai metafor dalam menuangkan karya mereka sehingga sulit dipahami. Ada juga yang terjerumus ke dalam bahasabahasa simbolik yang sulit dimengerti. Bahkan ada yang memilih menuangkannya dalam bentuk prosa dan puisi sehingga refleksi Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 12 filosofisnya nyaris hilang tertutupi keindahan gaya bahasa yang terlalu artistik dan emosional. 3. Menyadarkan para praktisi pendidikan bahwa Timur dan dunia Islam juga kaya dengan kreativitas intelektual yang pantas untuk dilihat, dihargai, diapresiasi, serta diberi kedudukan yang sejajar dengan tradisi intelektualitas yang berkembang di Barat. 1.6. Metode Penelitian Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu filsafat yang berimbas pada semakin luasnya kajian yang dicakup, wajar jika metode penelitian dalam ilmu ini juga bersifat dinamis. Oleh sebab itulah, bisa dimaklumi jika ada kalangan yang berpendapat bahwa dalam ilmu filsafat, metode penelitian tidak perlu dirumuskan secara praktis. Alasannya, objek ilmu filsafat tidak semata-mata data empiris, sehingga metode dalam penelitian filsafat akan ditemukan sendiri dalam proses penyusunan karya ilmiah tersebut.(Kaelan, 2005, 7). Akan tetapi, mengingat filsafat dewasa ini sudah menjadi disiplin ilmu tersendiri di samping ilmu-ilmu pengetahuan lain yang dicirikan dengan koherensi, sistematis, radikal, dan, rasional, maka metode penelitian menjadi instrumen penting yang sangat urgensif. Atas dasar itulah, dalam menyusun karya ilmiah ini, penulis memilih salah satu metodologi yang berkembang dalam filsafat Barat untuk dijadikan sebagai panduan, yaitu fenomenologi Edmund Husserl. Metodologi yang digagas oleh filsuf Jerman keturunan Yahudi ini— menurut hemat penulis—paling tepat untuk diterapkan dalam penyusunan karya ilmiah ini karena dua alasan. Pertama, secara pribadi, Husserl tercatat sebagai tokoh yang sangat apresiatif terhadap intuisi. Dan, fenomenologi ia proyeksikan sebagai suatu disiplin filosofis yang akan melukiskan segala bidang pengalaman manusia. Kedua, secara teknis, fenomenologi Husserl bisa dijadikan sebagai formula untuk menghasilkan penelitian yang rigorus. Walaupun keputusannya memasukkan konsep reduksi membuat sejumlah kalangan kecewa dan mengklaimnya telah terjebak dalam idealisme yang semula ia hindari, akan tetapi, saya bisa menerima alasan Husserl bahwa ralitas tidak pernah memberikan Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 13 seluruh profilnya secara total dan absolut. Oleh sebab itulah, untuk mendapatkan statemen yang apodiktis (tidak mengizinkan keraguan) dan absolut, reduksi mutlak diperlukan. (Bentens, 2002, 114) Setelah memutuskan penggunaan fenomeologi Husserl sebagai metode penelitian, maka penulis langsung menerapkan langkap-langkah metodis dalam metodologi ini sebagaimana dirangkum dan dipetakan dengan sangat cerdas dan aplikatif oleh Akhyar. (Akhyar, 2004, 194-232) Pertama, Deskripsi fenomenologis. Pada tataran ini, penulis berusaha menangkap fenomena secara intuitif, bebas dari asumsi, lepas dari interpretasi, serta berusaha menepis masuknya unsur subjetivitas. Jadi, semua karya yang ditulis oleh Suhrawardi (sejauh yang sampai pada penulis) dari yang bercorak diskursif hingga yang bernuansa intuitif dikaji secara mendalam tanpa memberikan pretensi dan penilaian apa pun! Dengan kata lain, penulis berusaha melihat objek itu apa adanya yang, dalam bahasa Husserl disebut Zurück zu den sachen selbst. Kedua, Memeriksa secara analitis. Pada taraf ini penulis menggunakan intuisi eidetis untuk mencari esensi suatu fenomena supaya bisa melihat hakikat fenomena secara langsung. Kongkritnya, berusaha menyelami rahasia yang terkandung di balik rangkaian naskah yang ditulis oleh Suhrawardi untuk menemukan esensinya. Ketiga, Hubungan antarhakikat didasarkan atas pengertian adanya hubungan antara satu fenomena dengan fenomena lain. Langkah ini tidaklah sesulit langkah pertama dan kedua. Sebab, penulis hanya berusaha memahami keterkaitan antara karya Suhrawardi yang satu dengan yang lain. Babak ini menjadi begitu mudah karena Suhrawardi secara langsung sudah memaparkan sendiri keterkaitan di antara karya-karyanya, agar diperoleh pemahaman yang benar dan akurat. Keempat, Mengamati cara penampakan fenomena. Dari 3 macam cara penampakan gejala yang dipetakan Akhyar, penulis lebih tertaik mengambil sudut pandang yang ketiga, yaitu tingkat kejelasan objek yang diselidiki, sehingga ada aspek yang dijadikan fokus perhatian dan ada yang dipinggirkan. (Akhyar, 2004, 231). Mengingat luasnya medan kajian serta banyaknya persoalan yang dikupas Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 14 Suhrawardi, maka, penulis mengunci satu persoalan dan memfokuskan perhatian kepadanya. Penulis coba mengonsentrasikan pengamatan pada konsep ilmu pengetahuan dan menyingkirkan tema-tema yang lain. Walaupun penulis tetap merasa dan yakin bahwa semua tema yang ditulis oleh Suhrawardi membentuk satu kesatuan utuh dan saling merajut antara yang satu dengan yang lain. Kelima, mengamati konstitusi fenomena dalam kesadaran. Apabila konsep epistemologi Suhrawardi diposisikan sebagai gunung, dalil Phytagoras, kampus UI, atau kota Jakarta seperti yang dicontohkan oleh Bertens dan Akhyar dalam buku masing-masing saat mengulas masalah konstitusi, secara teknis memang mustahil untuk memotret konsep tersebut secara silmultan. Lebih-lebih, konsep tersebut memang terserak dalam sejumlah buku, dalam arti Suhrawardi sendiri tidak memaparkannya secara tuntas dalam satu karya. Akan tetapi, dengan mengonstitusi konsep itu dalam kesadaran, berarti konsep itu bisa disintesakan dalam persepsi, dan tampilan yang terbagi dalam berbagai perspektif (terdapat dalam sejumlah buku) itu mengutuh dalam aktus kesadaran. Dengan demikian, konsep epistemologi Suhrawardi menjadi terpatri kuat dalam kesadaran sehingga bisa dipaparkan kapan pun dibutuhkan, sebagaimana kita bisa melukiskan kota Jakarta walaupun kita sedang berada jauh di daerah lain, atau bisa menyelesaikan persoalan matematika yang bisa dipecahkan dengan dalil Phytagoras. Keenam, Reduksi fenomenologis. Pada langkah yang ditolak oleh mayoritas fenomenolog termasuk Heidegger ini, penulis meletakkan konsep epistemologi suhrawardi dalam tanda kurung. Hasilnya, bagi objek yang dijadikan fenomen, konsep itu menjadi eviden yang absolut, sedangkan penulis selaku subjek mendapatkan kesadaran murni yang tidak berkeluasan dalam ruang dan waktu. Kesadaran—mengutip Bertens—tampak secara total dan langsung, sehingga memungkinkan untuk mengemukakan statemen-statemen yang apodiktis dan absolut tentang konsep itu. (Berten, 2002, 114). Kalau mengacu pada uraian Herbert Spielberg dalam The Phenomenological Movement yang dikutip Akhyar, sebenarnya masih ada satu langkah lagi dalam model penelitian fenomenologis, yaitu menafsirkan makna gejala atau fenomena. Sayangnya, mayoritas fenomenolog termasuk Husserl menolak langkah ini, dan hanya Heidegger yang menerimanya. Kata Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 15 "menafsirkan" pada langkah ketujuh ini membuat fenomenologi berkait-kelindan dengan hermeunetika. Oleh sebab itulah, fenomenologi Martin Heidegger lazim disebut fenomenologi-hermeunetika. Penulis sengaja tidak memasukkan langkah ketujuh ini karena 2 alasan. [1] Penulis berusaha untuk bersikap konsisten menerapkan metodologi yang dikonsepkan oleh Edmund Husserl tanpa menambahinya dengan konsep lain. Jadi, memasukkan langkah ketujuh sama artinya dengan mengubah metodologi dalam penyusunan karya ini, dari yang semula fenomenologi idealitik-realistik ala Husserl, menjadi fenomenologi-hermeunetik ala Hiedegger. [2] Motif di balik langkah ketujuh ini adalah mencoba menemukan makna yang tidak dapat dicapai melalui intuisi (Akhyar, 2005, 232). Padahal secara pribadi, penulis sudah merasa puas dan meyakini bahwa intuisi bisa menemukan makna apapun yang terkandung di balik fenomena. 1.7. Sistematika Penulisan Secara garis besar, penulisan karya ilmiah ini dibagi ke dalam 6 bab, dengan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab dengan uraian seperti berikut. Bab 1 : Membahas latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, serta metode penelitian lengkap dengan alasan masing-masing yang dipaparkan dengan tegas dan jelas. Bab 2 : Menguraikan riwayat hidup singkat Suhrawardi, karya-karyanya, atmosfer intelektualitas pada masa hidupnya, serta pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran Islam secara luas. Bab 3 : Menjelaskan secara ringkas bangunan pemikiran filosofis Suhrawardi yang tertuang dalam konsep filsafat iluminasi. Penjelasan dalam bab ini menjadi sangat penting karena Suhrawardi membangun teori filsafatanya secara integral dan utuh dengan satu tema, yaitu cahaya. Jadi, untuk memahami teori-teori partikular yang menjadi derivasi dalam sitem filsafatnya yang begitu megah, seperti teori tentang epistemologi, kosmologi, dan lain sebagainya, kita terlebih dahulu wajib memahami gagasannya secara utuh. Bab 4 : Menguraikan dimensi empiris dari ilmu hudhuri. Dalam bab ini penulis akan menguraikan pelbagai masalah dalam tindak dan proses mengetahui Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 16 yang berlangsung terhadap data-data indarwi yang nyata. Seperti cara membuat definisi yang sahih, serta teori penyaksian yang dalam terminologi Arab lazim disebut musyahadah. Bab ini akan diakhiri dengan uraian seputar teori objek yang berisi pemetaan terhadap realitas nyata, berikut metode ilmu hudhuri dalam mengetahui setiap objek tersebut. Bab 5 :Memaparkan dimensi intuitif ilmu hudhuri yang digagas oleh Suhrawardi, dan inilah inti dari karya ilmiah ini. Dalam bab ini dipaparkan segala masalah yang berkaitan dengan ilmu hudhuri, seperti pengetahuan tentang diri, langkah-langkah untuk mendapatkan ilmu hudhuri, serta tahapan apa saja yang harus dijalani supaya ilmu pengetahuan yang bersifat intuitif tersebut bisa disajikan secara ilmiah dan rasional. Bab 6 : Mengemukakan kesimpulan atas semua penjelasan dalam tesis ini, sekaligus memberikan analisa kritis terhadap konsep epistemologi Suhrawardi. Penulis merasa perlu memberikan analisa kritis karena semua teori pasti memiliki keunggulan dan kekurangan. Jika hanya mengupas kelebihan konsep epistemologi iluminasi ini tanpa memaparkan titik-titik kelemahannya, penulis khawatir akan terjebak pada subjektifisme ekstrem yang hanya mendewakan satu metode tertentu dan mengabaikan metode yang lain. Subjektifisme semacam ini hanya akan memiskinkan wacana, serta mengancam dinamika perkembangan ilmu pengetahuan. Pada bab ini juga, penulis memetakan posisi epistemologi yang digagas Suhrawardi di antara sekian banyak epistemologi yang dikembangkan oleh para pemikir, baik di Barat maupun di Timur. Terakhir, penulis memberikan rekomendasi untuk kajian lebih lanjut guna memantik hasrat para penggiat filsafat mengkaji pemikiran-pemikiran pendiri madzhab iluminasi ini. Jelasnya, semua bab dalam karya ilmiah ini disusun secara gradual, dimulai dari penjelasan-penjelasan yang bersifat umum, baru kemudian menukik ke inti permasalahan, lalu diakhiri dengan penutup dan penilaian. Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 BAB 2 BIOGRAFI SINGKAT SUHRAWARDI 2.1. Latar Belakang Sosio-Historis Sebelum lebih jauh mengupas tentang biografi Suhrawardi, penulis ingin menginformasikan bagi para peminat studi filsafat iluminasi bahwa, sumber yang paling akurat, representatif, dan dapat dipercaya yang melukiskan perjalanan hidup Suhrawardi adalah dua buku yang berjudul Nuzhah al-Arwah dan Rawdhah al-Afrah. Mengapa? Karena keduanya ditulis oleh Syamsuddin Muhammad alSyahrazuri, murid sekaligus komentator karya-karya Suhrawardi yang diyakini benar-benar memahami sejarah hidup sekaligus pemikiran filsuf asal Persia tersebut. Suhrawardi lahir pada tahun 549 H./1153 M. di Suhraward, sebuah kampung dekat Zinjan di Iran barat laut yang banyak melahirkan tokoh-tokoh Islam. Nama lengkapnya adalah Abu al-Futuh Yahya bin Habasyi Amirak alSuhrawardi. Ia memiliki sejumlah gelar, di antaranya; Syihab al-Din, Syaykh alIsyraq, dan al-Maqtul. Sebagaimana para pemikir besar lain yang mengembara ke daerah yang memiliki peradaban besar, Suhrawardi tidak tinggal diam dan menetap di kampung halamannya. Ia merantau ke sejumlah negeri untuk menggali khazanah ilmu pengetahuan; dari Yunani klasik hingga Islam. Maragha di Azarbeijan, Isfahan di Iran Tengah, Anatolia, Damaskus di Syiria, serta Aleppo adalah kotakota kaya peradaban yang disinggahinya. Sayang, sejauh penelusuran penulis, tak ada sumber lengkap yang menerangkan nama-nama besar yang dijadikan "tambang emas pengetahuan" oleh Suhrawardi. Padahal, ilmu pengetahuan yang dikajinya cukup luas dan beragam. Dari fiqh, tafsir, ilmu kalam, mantiq, tasawuf, hingga filsafat.(Manshur, 1996, 137) Suhrawardi mengawali pendidikannya di Maragha kepada Majd al-Din alJili bersama Fakhr al-Din al-Razi. Di kota yang kemudian terkenal karena lahirnya Nashir al-Din al-Thusi yang membangun observatorium pertama dalam Islam ini, ia belajar filsafat, hukum, dan teologi. Setelah itu, ia pergi ke Isfahan untuk memperdalam studinya kepada Fakhr al-Din al-Mardini (w. 294 H./1198 M.) dan Zhahir al-Din al-Qari dengan mengkaji al-Basya'ir al-Nasyiriyyah karya Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 18 ‘Umar bin Sahlan al-Sawi (w. 540 H./1145 M.). Terakhir, ia berguru kepada alSyafir Iftikhar al-Din. Menurut Hossein Ziai, Fakhr al-Din al-Mardini merupakan guru Suhrawardi yang paling penting dan sangat berpengaruh. (Ziai, 1998, 22) Sekali lagi, tidak ada sumber yang lebih lengkap dalam menguraikan petualangan Suhrawardi selama menuntut ilmu. Hampir semua referensi yang penulis telusuri hanya menyebutkan ketiga tokoh di atas sebagai guru Suhrawardi. Masalahnya sekarang, dengan prestasi yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, mungkinkah sosok seperti Suhrawardi hanya menimba ilmu dari tiga orang guru? Kemungkinan seperti itu memang selalu terbuka. Akan tetapi menurut hemat penulis, terlalu riskan jika Suhrawardi yang sangat cinta dan begitu haus akan ilmu pengetahuan, sudah merasa puas setelah belajar kepada tiga tokoh yang berbeda. Sebagai peretas jalan kebenaran yang haus ilmu pengetahuan, Suhrawardi tidak mencukupkan diri dengan mengetahui aspek teoritis dari ilmu yang dipelajarinya. Lebih jauh lagi, ia menerapkannya dalam kehidupan. Ia tidak pernah hanya memajang pengetahuan praktis yang diterimanya dalam bingkai wacana. Misalnya ilmu tasawuf, Suhrawardi tidak sekadar mempelajari teori dan metode untuk menjadi sufi, akan tetapi, ia langsung menyulap dirinya menjadi sufi sejati. Dia menjalani hidup dengan pola asketis sembari terus bertafakkur, berkontemplasi, beribadah, dan berfilsafat. (Drajat, 2005, 32) Keuletan yang ditopang penghayatan mendalam ini pada akhirnya mengantarkan Suhrawardi menjadi seorang filsuf sekaligus sufi. Dalam dirinya terkumpul dua keahlian secara integral; filsafat dan tasawuf. Kecemerlangan ini membuat penguasa Aleppo, Malik al-Zhahir terpukau dan terpaku. Selaku penguasa yang mencintai ilmu pengetahuan, filsafat, dan mistisisme, putra Shalah al-Din al-Ayyubi ini langsung mengundang dan meminta Suhrawardi tinggal di istananya. Gayung pun bersambut, Suhrawardi menerima undangan ini sekaligus mengakhiri petualangannya di Aleppo. Di sanalah kecerdasannya benar-benar terbukti dan teruji. Dalam diskusi-diskusi yang dihadiri sejumlah pakar dalam berbagai disiplin ilmu, ia mampu menunjukkan kepiawaiannya dalam Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 19 mengelaborasi teori filsafat dan tasawuf sehingga mampu mengalahkan pakar dan ulama mana pun! (Drajat, 2001, 13) Argumentasi-argumentasi elaboratif Suhrawardi tersebut, di satu sisi memang membuatnya semakin dekat dengan penguasa. Namun di sisi lain membuat ulama yang dengki kepadanya semakin cemas. Buah kecemasan ini adalah surat yang mereka kirimkan kepada Sultan Shalah al-Din al-Ayyubi, yang berisi permintaan agar Suhrawardi dibunuh, dengan alasan ajaran-ajarannya sesat, bertentangan dengan agama, dan sangat berbahaya. Konon, ulama yang paling gencar meminta agar sultan Sultan Shalah al-Din segera mengeksekusi Suhrawardi adalah Qadhi al-Fadhil. Hossein Ziai merangkum fenomena ini seperti berikut: "Dalam tertemuan-pertemuan pribadinya yang berkembang luas, filsuf muda ini diceritakan telah menginformasikan kepada sang pangeran tentang filsafat barunya. Tak pelak lagi, kenaikan pesat Suhrawardi ke posisi istimewa bersinggungan dengan intrik dan kecemburuan istana yang lazim dijumpai dalam abad pertengahan. Bahwa hakim, wazir, dan ahliahli fiqh Aleppo tidak senang dengan status guru yang meroket dari tutor terkemuka itu, mustahil dapat membantu meringankan perkaranya." (Ziai, tt, 246) Atas dasar rasa hutang budi kepada para ulama yang memiliki andil besar mengusir tentara Salib dari Syiria, Sultan Shalah al-Din lantas memerintahkan putranya mengabulkan permintaan mereka. Maka, dengan berat hati, Malik alZhahir mengeksekusi Suhrawardi pada tahun 587 H./1191 M. Akhirnya, sosok jenius ini harus meninggal dalam usia yang relatif muda; 38 tahun! (Hitungan ini didasarkan pada tahun hijriyah. Jika hitungannya didasarkan pada tahun masehi, maka usia Suhrawardi saat meninggal adalah 36 tahun. Perbedaan ini terjadi karena jumlah hari dalam tahun hijriyah, 11 hingga 12 lebih sedikit dari tahun masehi). Karena matinya dieksekusi, para ulama kemudian menggelarinya alMaqtul. Sayangnya, tak ada informasi yang akurat mengenai metode yang digunakan untuk mengeksekusi Suhrawardi. Akibatnya, sejumlah pakar berbeda pendapat dalam menentukan eksekusi yang dijalani oleh Suhrawardi. Menurut alTaftazani, Suhrawardi dihukum gantung. Menurut Seyyed Hossein Nasr, ia meninggal di penjara tanpa sebab yang jelas. Annemarie Schimmel hanya Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 20 menyebutkannya tewas dipenjara. Sedangkan Abdul Hadi W.M meyakini bahwa Suhrawardi mogok makan dan berpuasa hingga wafat dalam tahanan. Terlepas dari kontroversi caranya menghembuskan nafas yang terakhir, setelah kepergiannya pun para cendekiawan memberikan penilaian yang berbeda seputar kematiannya. Bagi yang memandangnya sebagai pemikir besar yang membawa gagasan hebat, Suhrawardi adalah pahlawan yang wajib dihargai. Muhammad Iqbal misalnya, tokoh terkemuka dalam dunia filsafat ini jelas-jelas menyesalkan eksekusi Suhrawardi. Dalam disertasinya yang berjudul Metafisika Persia, ia menulis tentang Suhrawardi: Pemikir muda Persia itu dengan tenang menghadapi pukulan yang membuatnya menjadi martir kebenaran yang, sekaligus mengabadikan namanya. Para pembunuh telah berlalu, tetapi filsafat yang nilainya dibayar dengan darah masih tetap hidup dan menarik banyak minat para pendamba kebenaran. (Iqbal, 1988, 98) Sinisme Iqbal terhadap para eksekutor tersebut sebaliknya malah dipandang positif oleh Ahmad Amin, seorang pemikir Islam kontemporer yang juga banyak bergelut dengan dunia filsafat dan sufistik. Baginya, keputusan mengeksekusi Suhrawardi sangatlah tepat karena ajarannya tidak sejalan dengan nafas Islam. Gelar al-Maqtul yang berarti yang terbunuh atau yang tereksekusi yang ditasbihkan pada Suhrawardi oleh orang-orang setelahnya membuktikan bahwa gagasan filsuf muda itu memang bertentangan dengan agama. Dia beralasan bahwa, sekiranya ajaran Suhrawardi lurus, maka orang-orang akan menggelarinya sebagai al-Syahid. (Mahmud, tt, 442) Titik tolak yang dijadikan senjata untuk menuduh ajaran Suhrawardi menyimpang adalah sejumlah terminologi yang terkesan asing di telinga ulamaulama eksoteris, yang dalam hal ini adalah para teolog atau ahli fiqh. Misalnya, teori tentang anggelologi atau kemalaikatan yang dalam Hikmah al-Isyraq disebut hierarki cahaya horisontal (Thabaqat al-Ardh). Nyaris semua nama malaikat dalam hierarki ini adalah nama malaikat dalam tradisi Zoroaster, seperti Khurdad, Murdad, Urdibihist, dan Isfandarmudh. Suhrawardi hanya menyisakan satu nama untuk malaikat dalam tradisi Islam, yaitu Jibril, itu pun bukan sebagai penyampai wahyu, akan tetapi sebagai pemilik teurgi genus yang berpikir atau arketip kemanusiaan. Roh suci pemberi ilmu pengetahuan, pertolongan, kehidupan, dan Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 21 keutamaan bagi bentuk manusia yang paling sempurna. (Suhrawardi, 1993, 200201) Bagi kalangan esoteris-perennialis, penamaan malaikat versi Suhrawardi ini pasti bisa ditoleransi. Mengingat jika ditelusuri lebih jauh, istilah malaikat yang digunakan Suhrawardi sama sekali tidak mengacu pada malaikat dalam arti konvensional yang berlaku dalam tradisi Islam. Seperti kita ketahui, dalam ajaran agama Islam, ada 10 malaikat yang harus diketahui yaitu: [1] Jibril (penyampai wahyu). [2] Mika'il (pembagi rezeki dan penurun hujan). [3] Izra'il (pencabut nyawa). [4] Israfil (peniup sangkakala). [5] Munkar (penanya amal saleh dalam kubur). [6] Nakir (penanya perbuatan salah dalam kubur). [7] Raqib (pencatat perbuatan baik). [8] ‘Atid (penulis perbuatan keji). [9] Malik (penjaga neraka). [10] Ridwan (penjaga surga). Sedangkan malaikat dalam konteks ini agak mirip dengan dunia idea Plato, kendati tidak sama persis. Tujuan Suhrawardi menggunakan istilah-istilah itu adalah untuk mengabadikan hikmah-hikmah keagamaan Persia pra-Islam dengan filsafat Yunani, sejalan dengan konsep Islam. (Drajat, 2001, 64) Jika diselidiki lebih jauh, pengeksekusian Suhrawardi sejatinya sarat muatan politis dan kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Dengan kata lain, permintaan para ulama eksoteris agar Suhrawardi dibunuh bukan semata-mata karena ajarannya yang beraroma esoteris dan sarat dengan simbol. Akan tetapi, karena mereka cemburu dan merasa tersaingi oleh tampilnya filsuf muda berbakat tersebut. Terobosan Suhrawardi yang asing dan baru ini, menurut Seyyed Hossein Nasr didasarkan pada keyakinan bahwa hikmah Tuhan bersifat universal dan perenial. Tuhan menurunkan hikmah melalui Hermes yang kemudian terbagi dua cabang; cabang Persia dan Mesir. Cabang Mesir kemudian menyebar ke Yunani yang pada gilirannya masuk ke dalam tradisi Islam bersama cabang Persia. Pada titik inilah, Suhrawardi menyebut dirinya sebagai pemersatu kedua cabang hikmah tersebut; yakni al-hikmah al-ladunniyyah dan al-hikmah al-‘athiqah. Seyyed Hossein Nasr memetakan alur percabangan hikmah tersebut hingga bermuara pada Suhrawardi seperti berikut ini: (Nasr, 1969, 61) Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 22 Hermes Agathedemon (Syits) Asclepius Para pendeta raja Iran Pythagoras Kayumart Empedokles Faridun Plato (dan Neo-Platonis) Kai Kusraw Dzu al-Nun al-Mishri Abu Yazid al-Bhistami Abu Sahl al-Tustari Manshur al-Hallaj Abu al-Hasal al-Kharraqani Suhrawardi Berdasarkan skema di atas, Seyyed Hossein Nasr menyimpulkan bahwa ada lima sumber pengetahuan yang membentuk pemikiran Suhrawardi. Pertama, pemikiran-pemikiran sufisme, khususnya al-Hallaj (858 H/913 M) dan al-Ghazali (1058 H/1111 M). Misykat al-Anwar, salah satu karya al-Ghazali yang menjelaskan adanya hubungan antara cahaya dan iman, mempunyai pengaruh langsung kepada Suhrawardi. Kedudukan al-Ghazali sebagai figur multi talenta, yaitu sebagai filsuf dan sufi nampaknya mengharuskan penulis menegaskan posisinya berkaitan dengan terminologi cahaya yang ia gunakan dalam Misykat al-Anwar. Tujuannya, supaya tidak timbul kesan bahwa pendiri awal filsafat cahaya adalah al-Ghazali, bukan Suhrawardi. Dalam karya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Sumber Segala Cahaya (Jakarta, Hikmah, 2001) tersebut, al-Ghazali memang terlihat begitu obsesif menggunakan metafor cahaya. Baginya, cahaya adalah simbol keindahan spiritual yang tak terperi. Dengan menyaksikannya, seseorang akan membumbung tinggi menaiki derajat-derajat ketinggian Ilahiah. Sayangnya, al-Ghazali masih belum sempat mengolah lebih jauh apa yang dituliskannya. Di tangannya, "cahaya" masih menjadi metafor dari sebuah spekulasi filsafat, dan bukan jantung filsafat itu sendiri. Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 23 Kedua, pemikiran fisafat peripatetik Islam, khususnya filsafat al-Farabi dan Ibn Sina. Meski Suhrawardi mengkritik sebagiannya, tetapi ia memandangnya sebagai azas penting dalam memahami keyakinan-keyakinan iluminatif. Tokoh yang kedua ini nampaknya berhasil dengan gemilang menancapkan pengaruhnya dalam diri Suhrawardi meskipun dalam beberapa kesempatan ia diserang dengan penuh gairah. Malah secara terbuka Suhrawardi menyatakan bahwa filsafat peripatetik merupakan salah satu unsur penting filsafat iluminasi, oleh sebab itulah, ia kemudian menulis al-Talwihat sesuai dengan metode peripatetik, lalu menyarankan para pembacanya untuk mengkaji kitab tersebut sebelum mengkaji Hikmah al-Isyraq. (Suhrawardi, 1993, 484) Ketiga, pemikiran filsafat pra-Islam, yakni aliran Pythagoras (500-580 SM), Platonisme dan Hermenisme sebagaimana yang tumbuh di Alexandria, kemudian dipelihara dan disebarkan ke Timur Dekat oleh kaum Sabean Harran. Sebagai sosok yang menempati singgasana tertinggi dalam skema Nasr, Hermes tentulah figur penting yang harus diperhitungkan. Dalam The Encyclopedia of Religion, Hermes Trismegistos oleh sejarawan Yunani klasik diidentifikasi sebagai Thot, dewa kebijaksanaan Mesir. Karena itu, pada abad ke-2 SM, Hermes dipuja dengan julukan megistos kai theos megas Hermes (dea tertinggi dan termulia, Hermes yang agung). Kata Trismegistos di belakang namanya masih diperselisihkan. Ada yang memaknainya sebagai tiga wajah yang mengacu pada kenabian, hikmah, serta kekuasaan yang dimiliki Hermes, tapi ada juga yang mengatakannya sebagai nama keluarga, semacam marga. Jika dilihat dari ajaran-ajarannya, Hermes dapat dipastikan sebagai seorang filsuf dan manusia biasa, bukan dewa. Ini dibuktikan dengan menyebarnya ajaran-ajaran Hermes di tangan generasi penerusnya yang disebut kaum Hermetik. Disebutkan juga bahwa Hermes menimba hikmah dari gurunya, Poimandres-Nous, dan berdiskusi dengan murid-muridnya seperti Ammon dan Asklepios—cucu Asklepios-Imhouthes. Dan konos, Isis bersama putranya Horus pernah mengomentari ajaran-ajaran Hermes yang disampaikan oleh kakeknya, Kamephis. Dalam perkembangannya, para filsuf Muslim menafsirkan sosok Hermes sebagai Akhnukh atau Idris as. Nabi sekaligus ahli hikmah yang bertugas menerjemahkan "pesan-pesan langit" ke dalam bahasa manusia agar bisa Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 24 dipahami. Munculnya Hermenetisme disambut oleh kepercayaan religius Mesir, filsafat Yunani, Yudaisme, dan kemudian memunculkan prisca philosophia (filsafat primordial), prisca magia (mistisisme primordial), serta prisca theologia (teologi primordial) yang dipelajari secara ekstensif di Barat dan di Timur. (Eliade, tt, 287-293) Keempat, kebijaksanaan-kebijaksanaan Iran klasik. Di sini Suhrawardi mencoba membangkitkan keyakinan-keyakinan secara baru dan memandang para pemikir Iran klasik sebagai pewaris langsung hikmah yang turun sebelum datangnya bencana topan yang menimpa kaum Nabi Idris. Dan kelima, ajaran Zoroaster, khususnya yang berkenaan dengan simbolisme cahaya yang dilawankan dengan kegelapan serta terminologi malaikat-malaikatnya. Semua corak pemikiran yang berpengaruh terhadap Suhrawardi ini bisa dirangkum dalam skema berikut ini. (Nasr, 1969, 60-61) Pemikiran Sufisme - Manshur al-Hallaj - al-Ghazali Filsafat Peripatetik Islam - Al-Farabi - Ibnu Sina Filsafat Pra-Islam - Pytagoras - Platonisme - Hermenisme Iluminasi Suhrawardi Hikmah Iran Klasik Ajaran Zoroaster Berdasarkan keterangan ini, kita tahu bahwa pemikiran Suhrawardi didasarkan pada sumber-sumber yang beragam dan berbeda-beda—tidak hanya Islam tetapi juga non-Islam—meski secara garis besar bisa dikelompokkan dalam dua bagian; pemikiran filsafat dan sufisme. Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 25 Dengan menyatukan kedua corak pemikiran yang berbeda tersebut, Suhrawardi benar-benar menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ia berhasil menegakkan sebuah imperium filsafat baru yang kemudian dikenal dengan istilah filsafat iluminasi. Kehebatannya dalam mengawinkan al-hikmah al-bahtsiyyah (penalaran diskursif) yang biasanya identik dengan para filsuf, dengan al-hikmah al-dzawqiyyah (metode eksperimental) yang selalu dikaitkan dengan kaum sufi, telah melahirkan teori baru yang benar-benar original. Kelihaiannya memadukan visi sufistik dan penalaran filosofis ini membuat dirinya layak disejajarkan dengan filsuf besar yang lain; semisal Ibn Sina atau Ibn Rusyd. Al-Syahrazuri bahkan memberikan pujian yang luar biasa berkaitan dengan kecerdasan ini. Dengan tegas ia mengatakan bahwa tak seorang pun yang dapat menggabungkan yang teoritis dan yang praktis dengan kecanggihan yang demikian sempurna. (Fakhri, 1986, 5) Pujian ini memang layak ditasbihkan kepada Suhrawardi, mengingat teorinya sukses menghilangkan dahaga pengetahuan yang berbeda. Pertama, para filsuf yang melulu berkutat dengan nalar diskursif yang kering kerontang. Dan kedua, para sufi yang kesulitan menerangkan pengalaman intuitif mereka yang sangat personal. 2.2. Hasil Kreativitas Intelektual Suhrawardi merupakan pemuda yang dinamis, progresif, dan sangat produktif. Kendati usianya tergolong pendek, namun, karya yang dihasilkannya sungguh luar biasa. Tidak hanya dari segi kuantitas, namun juga dari segi kualitas. Seyyed Hossein Nasr mencatat ada sekitar 50 tulisan yang ditinggalkan Suhrawardi, baik dalam bahasa Arab maupun bahasa Persia. (Nasr, 1969, 58). Manuskrip karangan Suhrawardi yang bisa diselamatkan saat ini tersimpan di perpustakaan Turki, India, dan Iran. Seyyed Hossein Nasr membagi karya-karya Suhrawardi ke dalam lima kategori. Pertama, buku-buku mengenai filsafat Peripatetik sebagaimana interpretasi dan modifikasi Suhrawardi sendiri. Kategori ini terdiri dari 4 buku besar yang—semuanya—ditulis dalam bahasa Arab. 1. Al-Talwihat al-Lawhiyyat al-‘Arsyiyyat (Pemaparan Rahasia dan Mahligai Tuhan). Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 26 2. Al-Muqawamat (Pembelaan). 3. Al-Masyari‘ wa al-Mutharahat (Jalan dan Dialog). 4. Hikmah al-Isyraq (Teosofi Iluminasi). Kedua, buku-buku tipis yang sebagian isinya menguraikan isi keempat buku di atas dengan bahasa yang sederhana. Kategori ini terdiri dari 7 buku yang ditulis dalam bahasa Arab dan Persia. 1. Hayakil al-Nur (Altar-altar Cahaya). 2. Al-Alwah al-‘Imadiyyah (Catatan Pilar-pilar Agama). 3. Risalah fi al-Isyraq (Risalah Seputar Iluminasi). 4. Partaw-namah, Fi I‘tiqad al-Hukama' (Keyakinan Para Filsuf). 5. Al-Lamahat fi al-Haqa'iq (Seberkas Cahaya Kebenaran). 6. Ma‘rifah Allah (Pengetahuan Tuhan) Yazdan Shinakht. 7. Bustan al-Qulub (Taman Hati). Ketiga, buku-buku singkat bermuatan sufistik yang sarat dengan simbol dan lambang. Novel-novel yang berisi uraian seputar perjalanan jiwa di jagat raya dalam usaha mencapai Tuhan ini hampir semuanya ditulis dalam bahasa Persia; hanya sedikit yang berbahasa Arab. Kategori ini terdiri dari 8 buku. 1. Al-‘Aql al-Ahmar (Akal Merah). 2. Aql-i Surkh, Ashwat al-Ajnihat Jibra'il (Suara Sayap Jibril). 3. Awaz-i Par-i Jibra'il, Qishshah al-Ghurbah al-Gharbiyyah (Kisah Pengasingan Barat). 4. Lughat al-Naml (Bahasa Semut) Lughat-i Muran. 5. Risalah fi Halah al-Thufuliyyah (Risalah Tentang Keadaan Anak). 6. Yauman Ma‘a Jama‘at al-Shufiyyin (Sehari Bersama Sufi) Ruzi ba Jama‘at-i Sufiyan. 7. Risalah fi al-Mi‘raj (Risalah Tentang Mi'raj). 8. Taghrid al-Simurgh (Senandung Simurgh) Safir-i Simurgh. Keempat, buku-buku yang berisi komentar atau terjemahan karya-karya filsafat klasik serta agama kuno. Kategori ini terdiri dari 3 buku. 1. Risalah al-Thayr (Risalah Burung). Buku ini sejatinya adalah karya Ibn Sina yang diterjemahkan ke dalam bahasa Persia. Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 27 2. Isyarah (Saran), komentar terhadap karya Ibn Sina dengan judul yang sama. 3. Risalah fi al-‘Isyq (Risalah Tentang Cinta). Buku ini ditulis berdasarkan karya Ibn Sina dengan judul yang sama. Kelima, buku yang berisi doa-doa yang pada abad pertengahan dikenal dengan Kutub al-Sa‘at, namun al-Syahrazuri menyebutnya dengan al-Waridat wa al-Taqdisat (Doa dan Penyucian). (Nasr, 1969, 58-59). Selain Nasr, Louis Massignon juga melakukan pengelompokan terhadap karya-karya Suhrawardi. Secara sederhana, ia membagi karya Suhrawardi ke dalam tiga kategori. Pertama, karya yang ditulis di masa mudanya. Meliputi; alAlwah al-‘Imadiyyah, Hayakil al-Nur, dan al-Rasa'il al-Shufiyyah. Kedua, yang ditulis semasa menggeluti filsafat Peripatetik. Meliputi; al-Talwihat al-Lawhiyyat al-‘Arsyiyyat, al-Lamahat fi al-Haqa'iq, al-Muqawamat, al-Masyari‘ wa alMutharahat, dan al-Munajat. Ketiga, karya yang ditulis di masa-masa akhir hidupnya saat sudah terpengaruh oleh aliran Neo-Platonis dan Ibn Sina. Meliputi; Hikmah al-Isyraq, Kalimah al-Hukama', dan Fi I‘tiqad al-‘Ulama'. Pengelompokan ini terlalu simplisistis dan kurang akurat. Pasalnya, karya Suhrawardi tidaklah seminim yang diklasifikasikan Massignon. Makanya, Nasr menilai bahwa Magsignon keliru dalam memetakan karya-karya Suhrawardi. Menurutnya, Massignon terlalu tergesa-gesa dalam melakukan studi sehingga menghasilkan kesimpulan yang kurang valid. Massignon sendiri mengamini kritik Nasr ini dengan mengatakan bahwa pengelompokan ini sebenarnya adalah penjajakan awal yang ia lakukan berdasarkan penelitian singkatnya terhadap tulisan-tulisan Suhrawardi. Dengan kata lain, klasifikasi itu ia lakukan berdasarkan pengetahuannya terhadap buku-buku Suhrawardi secara sepintas, yang ia temukan di perpustakaan Istanbul dan kota-kota lain. (Nasr, 1987, 269) Tidak semua karya Suhrawardi berhasil diselamatkan, dan tidak semua yang terselamatkan sudah diterbitkan. Dalam usia yang relatif singkat, Suhrawardi mampu menghasilkan karya banyak dan beragam. Menurut Abdul Hadi W.M., karya-karya filsafat Suhrawardi jauh melampau usianya yang pendek. (Hadi WM, 214) Jadi, tidak menutup kemungkinan, karya itu akan berlipat ganda sekiranya usianya lebih panjang. Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 28 2.3. Atmosfer Keilmuan Pada Masa Suhrawardi Apabila kita membuat sketsa tentang atmosfer keilmuan pada masa Suhrawardi kemudian menimbang terobosan dan kejeniusan gagasannya, rasanya tidak berlebihan jika kita katakan dia sebagai figur besar yang hidup pada masa yang tepat, the rigth time in the rigth time. Ada dua alasan yang bisa kita jadikan sebagai pengukuh hipotesa ini, di mana keduanya berkembang pada sisi yang berbeda. Pertama, Suhrawardi hidup pada abad ke-12, sebuah periode di mana etos intelektual Islam mulai menunjukkan tanda-tanda kejenuhan. Fenomena ini ditandai dengan keengganan pemikir Muslim untuk melanjutkan tradisi berpikir filosofis seperti yang dikembangkan oleh para pendahulu mereka seperti al-Kindi (801-873 M), al-Razi (865-950 M), al-Farabi (870-950 M), atau Ibnu Sina (9801037 M). Gerakan intelektualitas dalam dunia Islam yang dimulai sejak dinasti Abbasiyah mengambil alih otoritas politik kaum Muslimin dari dinasti Umawiyah, tepatnya ketika dinasti yang berpusat di Baghdad ini menggalakkan penerjemahan karya-karya besar berbahasa Yunani, Syiria, Sanskrit, atau Pahlevi ke dalam bahasa Arab sepanjang beberapa abad, kelihatannya akan segera mencapai puncaknya. Lebih-lebih setelah al-Ghazali menulis kritiknya terhadap filsafat melalui karyanya yang berjudul Tahafut al-Falasifah. Rasanya adalah tidak adil jika kita menimpakan kesalahan di balik berkurangnya minat kaum Muslimin terhadap filsafat pada periode ini pada sosok al-Ghazali seorang, dan tidak menyelidiki faktor-faktor lain yang tidak menutup kemungkinan juga menjadi penyebab merebaknya iklim negatif ini. Salah satunya adalah kajian filsafat itu sendiri. Seperti telah diketahui bersama, corak kajian filsafat sebelum Suhrawardi disominasi oleh aliran peripatetik—dalam bahasa Arab biasa disebut Masysya'iyun—yang sangat mendewakan nalar diskursif. Istilah peripatetik sendiri berasal dari bahasa Yunani peripatein yang berarti berkeliling atau berjalan-jalan. Menurut Majid Fakhry, dalam tradisi Yunani, kata ini juga bisa mengacu pada suatu tempat di serambi gedung olahraga di Athena tempat Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 29 Aristoteles mengajar murid-muridnya sambil berjalan-jalan. (Fakhry, 1988, 1274). Walaupun menurut Louis Ma'luf, metode ini sejatinya digunakan untuk pertama kali oleh Protagoras, namun pada perkembangannya lebih populer di tangan Aristoteles, sehingga kata peripatetik tidak hanya mengacu pada cara mengajar Aristoteles, tapi secara lebih luas juga mengacu kepada corak filsafatnya. (Ma'luf, 1997, 764) Penulis tidak memungkiri jika dikatakan bahwa peripatetisme di tangan filsuf Muslim sudah mengalami perluasan objek kajian, dan tidak hanya terbatas pada pemikiran Aristoteles, tapi sudah merupakan sintesa antara ajaran-ajaran Aristoteles, Plato, Plotinus, plus ajaran-ajaran Islam sendiri, akan tetapi tak seorang pun juga bisa mengingkari bahwa kata peripatetik ini sangat identik dengan corak berpikir Aristoteles, sehingga setiap kali kata itu disebut oleh Suhrawardi dalam karya-karyanya, titik acuan yang paling benar adalah para filsuf Muslim yang berafiliasi atau mengembangkan gaya pikir Aristotelian. Dalam dunia Islam, aliran peripatetisme ini berkembang dengan sangat fantastis dan mengalahkan aliran mana pun. Terhitung sejak al-Kindi bergabung dalam Bait al-Hikmah—lembaga penerjemahan bentukan dinasti Abbasiyah—di Baghdad dan menerjemahkan karya-karya filsafat Yunani, pemikiran Aristoteles begitu dalam memengaruhi corak berpikir para ilmuwan Muslim. Hal ini tentu saja tak lepas dari jasa al-Kindi yang berkesempatan bersentuhan langsung dengan teks-teks klasik itu dalam bahasa aslinya, untuk kemudian menulis sejumlah karya yang bercorak sama seperti gaya berfilsafat Aristoteles. Silakan cermati penilaian Majid Fakhry berikut: "Maka Satu Yang Benar adalah Yang Pertama." Pandangan ini berasal dari filsafat Aristoteles, tetapi Unmovable Mover-nya Aristoteles diganti dengan Sang Pencipta. (Fakhry, 1995, 15) Sejak al-Kindi mengemukakan pandangan-pandangan filosofisnya, banyak filsuf Muslim berikutnya seolah terkurung dalam penjara suci yang bernama aliran peripatetisme. Tercatat, tokoh-tokoh seperti al-Farabi dan Ibnu Sina seakan merasa nyaman berteduh di bawah payung Aristotelianisme ini. Walaupun di samping keduanya, tidak sedikit pula yang lebih tertarik mendalami dan Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 30 mengembangkan filsafat Platonian. Namun yang jelas, pengaruh dan gelegar aliran kedua ini tidaklah sedahsyat aliran yang pertama, aliran peripatetisme. Apabila dipandang dari popularitas dan besarnya pengaruh aliran peripatetisme, barangkali tidak berlebihan jika kita asumsikan bahwa kajiankajian filsafat yang marak selama kurang lebih selama 4 abad—terhitung sejak masa al-Kindi hingga Suhrawardi—didominasi oleh tema-tema yang menjadi lingkup kajian peripatetisme. Lamanya masa kejayaan aliran peripatetisme inilah yang mungkin sedikit demi sedikit menyelusupkan kebosanan di kalangan para peminat filsafat di dunia Islam. Mereka mulai jenuh dengan penalaran diskursif dan metode analitis logis yang sangat bertumpu pada kekuatan olah pikir dalam memperoleh pengetahuan atau menyelesaikan problem filosofis. Padahal, metode ini merupakan merek dagang peripatetisme yang sangat laku di pasaran. Para peminat filsafat tersebut seolah merasakan dahaga yang amat sangat terhadap metode baru yang berbeda dengan yang ditawarkan oleh Aristotelianisme. Pada masa itu, sebenarnya sudah ada metode lain dalam menggapai kebenaran dan mencapai kebijaksanaan yang tidak mengandalkan kekuatan rasio. Metode ini lazim disebut hikmah dzauqiyah, seni olah rasa yang bertumpu pada intuisi dan mistisisme. Sayangnya, sebelum kedatangan Suhrawardi, metode ini tak kunjung bisa disistematisir secara rapi lengkap dengan argumen-argumennya yang logis dan rasional. Akibatnya, metode yang subur di kalangan sufi ini lebih dipandang sebagai letupan-letupan emosional yang dihasilkan dari ekstase spiritual yang sangat subjektif, dan tak bisa diturunkan ke dalam wilayah ilmu pengetahuan yang bisa dinikmati oleh semua orang secara luas. Tragisnya lagi, ketika coba dituturkan, pengalaman spiritual ini tertuang dalam premis-premis aneh yang jika dipahami secara telanjang dan apa adanya, bukan hanya tidak masuk akal, lebih jauh lagi bisa dikategorikan sebagai ungkapan murtad dan kafir. Ungkapan-ungkapan kontroversial yang dilontarkan Manshur al-Hallaj rasanya cukup untuk dijadikan contoh dalam kasus ini. Telah berbaur jiwa-Mu dalam jiwaku, laksana berbaurnya khamer dan air bening. Bila menyentuh-Mu, tersentuhlah aku. Sebab, engkau adalah aku dalam segala hal. (Mansur, 2002, 112) Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 31 Di tengah dahaga intelektual inilah, Suhrawardi datang membawa konsepkonsep filsafat yang merupakan sintesa dari kedua jenis kebijaksaan yang sebelumnya sudah populer di tengah-tengah masyarakat Islam. Kebijaksaan analitis yang diwakili para pengikut aliran peripatetik, dan kebijaksanaan intuitif yang direpresentasikan para sufi dan mistikus. Suhrawardi kemudian menyebut teori filsafatnya sebagai filsafat iluminasi. Walaupun tidak secara ekspisit dinyatakan bahwa motif yang memicunya mengutarakan pandangan filsafat iluminasi adalah mengatasi kejenuhan intelektual dunia Islam yang mulai mewabah, namun Suhrawardi secara tegas mengatakan bahwa teori-teori filsafatnya ditujukan untuk mengoreksi pelbagai teori dalam filsafat peripatetik yang menurutnya, tidak benar dan wajib diluruskan. Tidak sedikit halaman dalam Hikmah al-Isyraq yang ia pergunakan untuk menyerang peripatetisme; baik ajarannya, ataupun tokohnya yang diwakili Ibnu Sina. Dalam pasal ke-15 misalnya, ia menulis kalimat judul "Fi Hadmi Qa'idah al-Masysya'yin fi al-Ta'rifat" yang artinya secara literal adalah "Runtuhnya Teori Filsuf Peripatetik tentang Definisi." Sedangkan kritiknya yang ditujukan langsung kepada Ibnu Sina tertuang dalam al-Masyari' wa alMutharahat saat Suhrawardi membahas masalah definisi. (Ziai, 1998, 97) Keberanian Suhrawardi menempuh jalan yang berbeda dari para filsuf yang sudah mapan ini, di luar dugaan berhasil menyulap grafik dunia filsafat kembali menunjukkan peningkatan. Kehebatannya dalam memadukan dua aliran besar dalam tradisi intelekstual Islam ini mendapat sambutan hangat dari para cendekiawan Muslim di masanya, walaupun faktanya tetap ada segelintir orang yang bersikap sinis terhadapnya. Tetapi secara garis besar bisa dikatakan bahwa kajian filsafat kembali dinamis setelah Suhrawardi memperkenalkan filsafat iluminasi. Kejeniusannya dalam merekonstruksi penalaran diskursif serta kemampuannya memberikan landasan praepistemik yang kokoh terhadap pengalaman mistik, tidak hanya membuatnya diterima secara aklamasi oleh kedua kutub aliran tersebut, lebih dari itu, sukses membuat filsafatnya tampil dalam wajah baru yang indah dan menarik sehingga bisa dikatakan sebagai teori filsafat yang khas Islam, bukan lagi filsafat Yunani yang diislamkan. Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 32 Kedua, seperti telah disinggung sedikit, Suhrawardi hidup setelah alGhazali menulis Tahafut al-Falasifah—sebuah karya yang memiliki kekuatan magis luar biasa untuk memalingkan minat generasi Muslim dari kajian filsafat, serta memilih bidang kajian yang lain, seperti yurisprudensi (ilmu fikih), linguistik (tata bahasa), tafsir, hadis, dan bidang keagamaan lain. Saat itulah, banyak kalangan yang menilai bahwa tradisi filsafat dalam dunia Islam sudah tamat dan berakhir! Penilaian negatif seperti ini tidak hanya berlaku di kalangan sarjana Barat, tapi juga seakan diamini oleh sarjana Muslim yang berwaasan sempit. Sebagai bukti, sekali lagi, silakan cermati buku-buku atau daftar silabi pengajaran filsafat Islam yang beredar luas di Indonesia, hampir semuanya menutup kajian pada tokoh yang bernama al-Ghazali. Kendati memperpanjang sedikit, rata-rata tak lebih dari sekadar membahas Ibnu Rusyd. Itu pun lebih disebabkan karena filsuf tersebut menulis kritik tajam terhadap Tahafut alfalasifah yang diberi judul Tahafut at-Tahafut. Tokoh-tokoh besar seperti Suhrawardi atau Mulla Shadra nyaris tak tersentuh, sehingga banyak peminat kajian filsafat Islam yang gamang atau bahkan buta dengan gagasan-gagasan kedua filsuf yang tersebut terakhir tadi. Jika dicermati secara saksama, kritik al-Ghazali terhadap filsafat sejatinya hanya tertuju pada satu aspek saja, yaitu aspek metafisika. Sementara aspek yang lain seperti logika, etika, filsafat agama, dan lain sebagainya, benar-benar luput dari kritik. Oleh sebab itulah, Amin Abdullah—guru besar kajian Islam IAIN Sunan Kalijaga dalam karyanya yang berjudul Studi Agama sangat menyayangkan pandangan turun-temurun yang dianut kaum Muslimin bahwa kritik al-Ghazali berlaku bagi semua aspek kajian filsafat, dan tidak hanya terbatas pada aspek metafisika saja. (Abdullah, 1999, 231) Pernyataan ini diamini oleh pemikir Muslim masa kini, Seyyed Hossein Nasr. Menurutnya, anggapan semacam itu hanyalah merugikan kaum Muslimin sendiri, khususnya kaum Sunni. Mengapa? Karena anggapan itu mengakibatkan timbulnya kesan stagnasi pemikiran filsafat di dunia Sunni. Dan, citra inilah yang dipelihara oleh para orientalis. (Nasr, 1978, 3) Terlepas pada kenyataan bahwa yang diserang al-Ghazali hanyalah aspek metafisika saja, dan serangan itu secara spesifik ditujukan kepada Ibnu Sina Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 33 semata, dan juga terlepas dari kesalahan kaum Muslimin dalam memahami dan menyikapi kritik ini, marilah kita melihat fakta sejarah yang ditimbulkan oleh karya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul yang sama tersebut: Tahafut al-Falasifah. Sejak Tahafut al-Falasifah tersebar ke publik, mayoritas Muslim Sunni mulai mengubah pandangan terhadap filsafat. Perhatian mereka benar-benar tersedot oleh penilaian al-Ghazali yang ketiga terhadap filsafat al-Farabi dan Ibnu Sina; yaitu kafir. Sekadar catatan, bagi al-Ghazali, pemikiran filsafat bisa dibagi 3 kelompok. [1] Yang tidak perlu disangkal, dengan arti dapat diterima. [2] Yang harus dipandang sebagai bidah atau heterodoksi. [3] Yang harus dipandang kafir. (Zar, 2004, 161) Ironisnya adalah, penilaian yang ketiga ini hanya didasarkan pada 3 pemikiran metafisika dalam filsafat Ibnu Sina yang meliputi, [1] Alam dan semua substansi bersifat azali dan abadi. [2] Tuhan tidak mengetahui hal-hal yang bersifat partikular. [3] Kehidupan dalam dunia eskatilogis hanyalah ruh semata. Artinya, kelak yang akan dibangkitkan di akhirat hanyalah ruh saja, tidak demikian dengan jasad. (Zar, 2004, 163) Tidak ada yang tahu pasti alasan mengapa kaum Sunni kemudian menganggap bahwa koreksi al-Ghazali ini berlaku universal terhadap seluruh pemikiran filsafat, dan tidak kepada salah satu aspeknya saja. Yang jelas, sejak saat itu mereka lantas bersikap lebih ekstrem dari al-Ghazali sendiri terhadap kajian filosofis. Suatu sikap yang menurut hemat penulis, lahir dari kajian yang tidak tuntas dan studi yang bersifat parsial terhadap karya-karya al-Ghazali sendiri. Karena kenyataan membuktikan bahwa sejumlah poin filsafat Ibnu Sina malah dijadikan sebagai dasar oleh al-Ghazali untuk mengembangkan suatu konsep pemikiran baru. Contohnya adalah teori tentang cahaya dan emanasi. Tentang hal ini, Yazdi menulis: Berdasarkan teori Ibnu Sina, al-Ghazali mengembangkan suatu uraian linguistik yang signifikan mengenai ungkapan "cahaya" yang layak diterapkan kepada Tuhan sebagai sumber cahaya, dan kepada eksistensi alam semesta sebagai cahaya emanatif yang terpancar dari Cahaya dari segala cahaya (Light of lights) (Yazdi, 2003, 54) Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 34 Kenyataan ini harus disadari lalu disikapi secara arif agar pandangan negatif terhadap filsafat dalam dunia Sunni yang masih terasa hingga saat ini benar-benar sirna. Sebab, inilah satu-satunya cara untuk mendobrak kemandegan tradisi berfilsafat di kalangan Sunni. Penulis katakan sebagai satu-satunya cara karena sampai saat ini sudah terlalu banyak pemikir dan cendekiawan yang bersusah payah meluruskan maksud dan tujuan penulis Tahafut al-Falasifah tersebut. Sayangnya, tak satu pun dari mereka yang berhasil. Bahkan, pemikir sekaliber Ibnu Rusyd yang menulis koreksi terhadap Tahafut al-Falasifah 2 abad setelah al-Ghazali meninggal juga tidak menuai apa-apa. Bagi kalangan Sunni— aliran terbesar dalam Islam, filsafat seolah menjadi disiplin yang haram untuk dipelajari karena bisa membuat seseorang menjadi murtad!? Saat nasib filsafat di dunia Islam berada di ujung tanduk inilah, Suhrawardi tampil ke permukaan membawa gagasan baru yang ia beri nama filsafat iluminasi. Walaupun secara genitas dan kultural Suhrawardi berasal dan dibesarkan oleh tradisi Syiah, namun keberaniaannya dalam mengutarakan gagasan-gagasannya secara lugas dan cerdas telah membawa selaksa berkah bagi umat Islam secara universal. Di antaranya adalah, mementahkan anggapan bahwa filsafat dalam dunia Islam sudah selesai karena telah mencapai puncaknya di tangan Ibnu Sina. Dengan kata lain, kemunculan Suhrawardi berikut sistem filsafatnya yang berbeda dengan Ibnu Sina adalah bukti nyata bahwa tradisi berpikir filosofis kaum Muslimin masih berkembang dan akan selalu melahirkan temuan-temuan baru yang tetap menarik untuk dikaji. Pencetusan gagasan baru dalam dunia filsafat seperti yang dilakukan Suhrawardi ini, merupakan sarana yang jauh lebih efektif untuk mengembalikan minat dan semangat kaum Muslimin guna mempelajari filsafat. Bahkan jauh lebih efektif dari yang dilakukan Ibnu Rusyd, yaitu menulis kritik balik terhadap alGhazali. Langkah seperti inilah yang seharusnya ditiru oleh segenap pemikir Muslim jika ingin mengembalikan kejayaan filsafat dalam dunia Islam. Menawarkan suatu konsepsi yang sama sekali berbeda dengan pelbagai konsep yang sudah dibangun oleh para filsuf sebelumnya. Tidak perlu lagi sibuk-sibuk mencari akar masalah di balik keengganan serta menurunnya hasrat mengkaji Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 35 filsafat, atau melakukan pelurusan terhadap pelbagai kritik tajam yang setiap saat selalu bermunculan dan dilakukan oleh kalangan Muslim sendiri. Cara seperti ini bukan hanya sudah terbukti tidak berhasil, alih-alih malah membuat para pengkaji filsafat itu sendiri terjebak dalam polemik pemikiran klasik yang takkan pernah ditemukan jalan keluarnya. Biarkan semua kritik itu menimpa filsafat. Malah anggaplah sebagai ornamen indah yang menghiasi dinamika pasang surut perjalanannya. Contohlah Suhrawardi yang berikap acuh terhadap kritik picisan itu, dan memilih untuk memberanikan diri mengutarakan teori baru yang terbukti berhasil memberikan pencerahan terhadap filsafat. Bukti yang menujukkan bahwa Suhrawardi bersikap acuh terhadap kritik seperti yang dilontarkan al-Ghazali adalah, dia tidak menyediakan satu kalimat pun dalam semua karyanya untuk memberikan tanggapan terhadap krtitik tersebut. Padahal, ia hidup sesudah al-Ghazali dan sudah barang tentu membaca karya-karyanya. Hal ini terlihat dari elaborasi terminologi cahaya yang sebelumnya sudah digunakan al-Ghazali, dan seperti pengakuannya sendiri, ia secara terbuka mengakui al-Ghazali sebagai salah seorang inspiratornya. Di samping itu, dalam sejumlah kesempatan ia secara terus terang mengkritik bahkan menyalahkan filsafat Ibnu Sina. Pada titik ini, ia sama seperti al-Ghazali. Akan tetapi, krtitik Suhrawardi kepada Ibnu Sina diarahkan kepada substansi pemikiran filsafatnya, bukan kepada unsur semantiknya seperti yang dilakukan al-Ghazali sebagaimana penilaian Mehdi Hairi Yazdi.(Yazdi, 2003, 54) Akibatnya, walaupun objek dan subjek yang dikritik adalah sama, yaitu Ibnu Sina, namun dampak yang dihasilkan dari kritik tersebut bertentangan secara diametral. Kritik yang dikemukakan al-Ghazali tidak bisa dipungkiri telah memberikan andil terhadap meredupnya tradisi filsafat di dunia Islam, sedangkan kritik Suhrawardi bisa diibaratkan seperti pupuk yang sangat berjasa dalam menyegarkan kembali tamanan filsafat yang sudah mulai layu tersebut. Sejak ia melemparkan gagasan filsafat iluminasinya, atmosfer keilmuan yang semula kering, miskin, dan kurang variatif karena mulai kehilangan salah satu poros kajiannya, yaitu filsafat, mulai bersemi, subur, dan semarak kembali. Tema dalam diskusi-diskusi di halaqah-halaqah keilmuan tidak lagi terbatas pada Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 36 masalah-masalah keagamaan seperti fikih, tafsir, atau hadis semata, tapi kembali meluas mencakup pemikiran filsafat. . 2.4. Pengaruh Suhrawardi Pada Perkembangan Pemikiran Islam Untuk menentukan pengaruh Suhrawardi terhadap pemikiran Islam tidaklah semudah yang dibayangkan. Mengapa? Karena kata pengaruh selalu bersifat netral yang konotasinya bisa dibawa positif tapi juga bisa dibawa negatif. Tergantung ke mana kata itu akan dibawa. Pada tataran ini, nilai objektivitas suatu karya ilmiah sangat dipertaruhkan. Timbulnya pelbagai kesalahpahaman dan penilaian negatif terhadap seorang tokoh atau suatu teori, biasanya lahir dari ketimpangan uraian mengenai pengaruh tokoh atau teori tersebut. Demikian juga sebaliknya, munculnya penyucian terhadap seorang figur atau pengkultusan atas suatu konsep, lazimnya lahir dari hal yang sama. Artinya, jika hendak membuat seorang tokoh dinilai memiliki pengaruh positif, maka kita cukup mengungkapkan sisi-sisi baiknya saja sembari memendam dalam-dalam sisi buruknya. Hukum yang sebaliknya berlaku jika ingin membuat suatu tokoh dikesankan negatif. Cukup memaparkan sejumlah cela dan keburukannya, sambil mengubur jasa dan sisi positifnya. Masalah lain yang berkaitan dengan pengaruh seseorang ini adalah, tidak adanya tolok ukur jelas yang bisa dijadikan pijakan untuk menentukan seseorang berpengaruh bagi orang lain atau tidak. Lebih-lebih dalam dunia filsafat. Kesamaan konsep atau kemiripan teori tidak bisa dijadikan landasan untuk mengklaim seseorang telah dipengaruhi seseorang. Bahkan, intensitas pergaulan yang terbingkai dalam relasi guru-murid pun terkadang sulit untuk menentukan apakah sang guru memberikan pengaruh kepada muridnya atau tidak. Semua orang tahu bahwa Aristoteles adalah murid Plato, namun apakah bisa dikatakan bahwa Aristoteles terpengaruh pikiran Plato? Jawaban untuk pertanyaan ini bisa ya, tapi juga bisa tidak. Tergantung dari sudut mana kita menilainya. Jika kita menilai gagasan-gagasan Plato telah dijadikan sumber inspirasi bagi Aristoteles untuk mengemukakan teori-teori yang berbeda, tentu jawabannya Plato telah berpengaruh pada diri Aristoteles. Tapi jika kita menilainya dari sudut Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 37 pendang perbedaan konsep antara keduanya, maka jawabannya pasti tidak. Sebab, ciri filsafat Plato sangat berbeda dari Aristoteles. Karena absurdnya kriteria dalam menentukan pengaruh inilah, penulis kemudian berinisiatif untuk menentukan kriteria sendiri atas pengaruh Suhrawardi terhadap pemikiran Islam. Yaitu, melihat besarnya minat para peneliti pemikiran Islam sesudahnya dalam mengkaji, melestarikan, serta mengomentari—baik yang bernada positif ataupun yang bernada negatif—hasil pemikiran Suhrawardi. Dengan menentukan kriteria seperti ini, kita cukup menelisik sejarah filsafat Islam sejak Suhrawardi hingga masa kini guna menemukan pelbagai indikator yang menandakan bahwa tokoh iluminasi ini memiliki gagasan jenius yang bukan hanya dikaji oleh generasi sesudahnya, tapi juga diajarkan, dipraktikkan, serta dijadikan sebagai mahakarya yang layak untuk diwariskan secara turun-temurun. Sesuai dengan pepatah yang mengatakan bahwa gagasan besar takkan padam meskipun ditinggal oleh penemunya, demikian juga dengan filsafat iluminasi Suhrawardi. Meskipun beliau dieksekusi, sejarah membuktikan bahwa filsafat iluminasi tidak mengikutinya ke liang lahat, tapi justru malah tersebar dan tertebar ke seluruh penjuru, jauh melintasi batas-batas geografis Aleppo—tempat sang penemu dihukum mati. Abad demi abad selalu ada peminat yang dengan serius belajar dan mengajarkan teori filsafat ini secara serius. Sebagai langkah awal, menurut Seyyed Hossein Nasr, pemikiran Suhrawardi berkembang pesat di daerah-daerah yang secara historis dan peradaban, memiliki latar belakang intelekstual yang sama. Persia dan sekitarnya merupakan kawasan yang secara keseluruhan sejalan dengan alam pikiran Suhrawardi. Perlahan namun pasti, langkah berikutnya filsafat iluminasi merambah anak benua India-Pakistan, Syiria, Anatolia, baru kemudian masuk ke Eropa walaupun sangat terlambat. (Nasr, 1993, 166) Untuk mengetahui besarnya pengaruh filsafat Suhrawardi terhadap para pemikir setelahnya, sumber yang paling lengkap dan akurat, menurut hemat penulis, adalah dua karya cendekiawan Muslim kontemporer yang sangat giat melakukan studi terhadap filsafat iluminasi. Pertama adalah The Islamic Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 38 Intelectual Traditional in Persia yang ditulis oleh Seyyed Hossein Nasr, serta Suhrawardi and the Scholl of Illumination karya Mehdi Amin Razafi. Menurut kedua sumber ini, figur yang paling penting dalam proses penyebaran pemikiran Suhrawardi yang pertama adalah Syamsuddin Muhammad al-Syahrazuri (w. 1281). Murid langsung Suhrawardi inilah yang menulis Syarah Hikmah al-Isyraq. Sebuah karya yang berisi komentar serta penjelasan terhadap istilah serta masalah-masalah pelik yang sulit untuk dipahami dalam karya gurunya yang berjudul Hikmah al-Isyraq. Di samping itu, ia juga menulis komentar terhadap kitab al-Talwihat yang merupakan karya penting lain dari sang guru. Selain al-Syahrazuri, figur lain yang menulis komentar terhadap al-Talwihat dan melakukan kajian serius terhadap pemikiran Suhrawardi adalah Sa'ad bin Manshur Ibnu Kammunah ( w. 1269). (Razafi, 1997, 122) Kedua murid Suhrawardi ini bukan hanya berjasa dalam meneruskan pemikiran gurunya, lebih dari itu, mereka jugalah yang memancing minat para pengkaji setelahnya terhadap filsafat iluminasi. Dengan kata lain, keduanyalah yang menjadi lidah penyambung pertama ajaran-ajaran Suhrawardi sehingga teori dan pemikirannya tersiar luas dan bisa kita nikmati hingga saat ini. Pada abad berikutnya, abad ke-14, sejumlah tokoh yang tertarik terhadap filsafat iluminasi mulai tumbuh subur laksana cendawan di musim hujan. Banyak kajian dan komentar terhadap Suhrawardi yang ditulis pada abad ini. Namun di antara sekian banyak tokoh tersebut, yang paling menonjol adalah Quthbuddin alSyirazi (w. 1311). Pada abad abad ke-15, filsafat iluminasi mengalami stagnasi sehingga tidak melahirkan figur penting yang menulis karya di bidang ini. Meskipun demikian, bukan berarti madzhab filsafat ini sudah tidak diminati lagi dan tidak dipelajari. Kajian terhadap pemikiran Suhrawardi tetap semarak dan menghiasi diskusi-diskusi filsafat di banyak tempat. Hanya saja, tidak ada tokoh besar yang menghasilkan karya penting untuk dijadikan rujukan tentang pemikiran Suhrawardi. Fenomena pasang surut semacam ini pada dasarnya adalah hal yang biasa dalam suatu tradisi pemikiran. Pada abad ke-16, filsafat iluminasi mulai menampakkan geliatnya kembali. Ada beberapa figur penting yang menulis karya-karya filsafat yang, Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 39 secara jelas menyiratkan besarnya pengaruh Suhrawardi di dalamnya. Di antaranya adalah Shadruddin Dasytaki dan anaknya Ghiyatsuddin Manshur Dasytaki (1541). Dia menulis Isyraq Hayakil al-Nur li Kasyf Zhulumat Syawakil al-Ghurur yang berisi komentar dan ulasan terhadap karya Suhrawardi yang berjudul Hayakil al-Nur. Menurut Ziai, keduanya termasuk tokoh yang menyiapkan landasan bagi filsafat iluminasionis di kalangan Syiah Persia. Di samping itu, tokoh penting lain di abad ini adalah Jalaluddin Muhammad bin Sa'aduddin ad-Dawwani (w. 1502). Dialah yang menulis Lawami' al-Isyraq fi Makarim al-Akhlaq dan Syawakil al-Nur fi Syarah Hayakil al-Nur. Karya yang tersebut terakhir ini merupakan ulasan terhadap karya Suhrawardi yang berjudul Hayakil al-Nur. (Ziai, 1998, 12) Pada abad ke-17, pemikiran Suhrawardi berhasil mendapatkan posisi yang penting di tengah percaturan dunia intelektual Islam. Pada masa ini, di kawasan Persia lahir Madzhab Isfahan yang dipelopori oleh Mir Muhammad Baqir Damad Husaini Astaradadi. (w. 1631). Tokoh yang memiliki banyak murid ini berperan besar dalam menyebarkan paham iluminasi. (Drajat, 2005, 62). Selain Mir Damad, masih banyak tokoh besar lain dalam madzhab Isfahan ini. Di antaranya adalah Syaikh Bahauddin Amili (w. 1622), kemudian juga Mir Abdul Qasim Findiriski (w. 1641) yang menulis Qashidah. Sebuah buku yang merupakan ringkasan atas Hikmah al-Isyraq karya Suhrawardi. (Razafi, 1997, 127). Kemudian juga Mulla Muhsin Faydh Kashani dan Muhammad Syarif Nizhamuddin al-Harawi. Apabila sesaat menoleh ke Barat, tepatnya ke Jerman pada tahun 1923 ketika Falix Weil mendirikan Institut für Sozialforschung yang para ilmuwannya kemudian disebut sebagai "Madzhab Frankfurt", maka kita akan mendapatkan sejumlah kesamaan dengan "Madzhab Isfahan" yang melegenda di Iran pada abad ke-17. Persamaannya adalah, [1] Kedua madzhab ini digawangi oleh sejumlah cendekiawan yang memiliki minat besar terhadap dunia filsafat. [2] Meskipun para cendekiawan yang berkiprah di dalamnya terdiri dari orang-orang yang memiliki keahlian spesifik yang berbeda, atau bahkan kecenderungan berfilsafat yang berbeda—seperti Friederich Polloch yang seorang ahli ekonom dan Walter Benjamin yang merupakan pakar susastra, ada kecenderungan besar di antara Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 40 mereka dalam mengistimewakan pemikiran Kalr Marx, sehingga kalangan mahasiswa kemudian menjuluki institut tersebut sebagai Café Marx (Bertens, 2002, 195) Dalam Madzhab Isfahan juga demikian, di antara mereka ada yang merupakan pakar Yurisprudensi semisal Syaikh Amili, dan ada juga yang merupakan mistikus seperti Faydh Kashani. Akan tetapi, mereka semua memiliki kesatuan sikap dalam mengistimewakan filsafat Iluminasi dan gagasan Suhrawardi. [3] Kedua madzhab ini memiliki pengaruh yang luas terhadap dunia ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kajian filsafat. Di samping persamaan ini, tentu saja juga ada perbedaan antara Madzhab Isfahan dan Madzhab Franfurt. Di antaranya adalah, Madzhab Isfahan terlalu fokus dalam dunia filsafat sehingga tidak menyentuh masalah-masalah sosial. Hal ini berbeda dengan Madzhab Franfurt yang, tujuan awal didirikannya saja adalah menyelidiki persoalan-persoalan sosial. (Bertens, 2002, 194) Di antara sekian banyak pemikir iluminasi pada abad ini, mungkin yang terbesar dan paling populer adalah Shadruddin al-Syirazi (w. 1640). Tokoh yang lebih dikenal dengan Mulla Shadra ini tidak hanya menulis komentar atau ulasan terhadap karya-karya Suhrawardi seperti yang dilakukan para filsuf sebelumnya, lebih dari itu, ia berhasil mengelaborasi filsafat iluminasi sedemikian rupa sehingga lebih komprhensif dan sempurna. Sejumlah pemikiran Suhrawardi yang dipandangnya kurang relevan, dikoreksi lalu diperbaiki. Karya terbesarnya adalah al-Asfar al-Arba'ah. Menurut Seyyed Hossein Nasr, dalam karya besar yang juga biasa disebut al-Hikmah al-Muta'aliyyah ini, Mulla Shadra dengan sangat cemerlang sukses mengelaborasi iluminasi yang diterima dari kesadaran spiritual dan ajaran wahyu dengan argumen yang rasional. Dengan prestasi ini, Shadra bisa dikatakan selangkah lebih hebat dibandingkan "guru"nya sendiri, Suhrawardi. Pasalnya, ketika filsafat iluminasi Suhrawardi masih merupakan kombinasi penalaran diskursif dengan intuisi mistik, maka Mulla Shadra telah melengkapinya dengan ajaran wahyu. Tentang prestasi ini, tanpa ragu Nasr mendaulat Mulla Shadra sebagai puncak aktivitas inteletual selama seribu tahun dalam dunia Islam. (Nasr, 1986, 312) Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 41 Gelegar kehebatan Mulla Shadra dalam menata ulang gagasan-gagasan Suhrawardi pada abad ini, di satu sisi memang membuat filsafat iluminasi menjadi aliran yang paling pupuler di kalangan pemikir Muslim, tapi di sisi lain justru menenggelamkan tokoh-tokoh penting yang juga serius mengkaji filsafat ini pada abad berikutnya, abad ke-18. Hal ini terbukti dengan tidak adanya tokoh besar yang "layak" diabadikan sebagai penyiar gagasan Suhrawardi pada abad ini. Nasr, Razafi, Ziai, serta para peneliti lain filsafat iluminasi masa kini tidak mencantumkan satu nama pun yang bisa dikatakan sebagai iluminasionis abad ini. Pada abad ke-19, filsafat iluminasi kembali terbit dan melahirkan tokohtokoh penting seperti Mulla Ali Nuri (w. 1830), Mulla Hadi Sabziwari (w. 1878) yang secara cerdas berhasil menulis ulasan-ulasan ringkas terhadap Hikmah alIsyraq Suhrawardi dan al-Asfar al-Arba'ah Mulla Shadra. Kemudian juga ada Hasan Lubnani, Muhammad Shadiq Ardistani, Mir Sayyid Hasan Taliqani yang mengajarkan wacana filsafat iluminasi di sekolah-sekolah, Muhammad Ridha Qumsyai yang secara akurat berupaya menggabungkan pemikiran iluminasi Suhrawardi, gnosis Ibnu Arabi, dan metafisika Mulla Shadra. (Razafi, 1997, 127134). Menurut Razafi, pada abad ini ada sejumlah tokoh penting yang layak diperhitungkan. Di antaranya adalah Mulla Abdullah Zumuni dan putranya Mulla Ali Zumuni. Penguasaan kedua tokoh penganut iluminasionisme ini terhadap wacana filsafat tidak bisa disepelekan. Hal ini terbukti dengan keberhasilan Mulla Ali Zumuni memenuhi permintaan penguasa untuk menulis karya yang mengulas pertemuan antara filsafat Islam dengan filsafat Barat, khususnya filsafat Imanuel Kant. (Razafi, 1997, 134). Sedangkan ayahnya, Mulla Abdullah Zumuni menulis Lama'at-i Ilahiyyah yang berisi uraian seputar pengaruh Suhrawardi dan Mulla Shadra terhadap para filsuf Muslim. (Razafi, 1997, 135) Pada abad ke-20, banyak para iluminasionis Muslim yang berjasa besar mengukuhkan kedudukan aliran filsafat ini di antara sekian banyak aliran filsafat yang seakan berlomba merebut simpati para pemikir. Di antaranya adalah Sayyid Husain Thabathaba'i (w. 1982), seorang ulama Syiah yang sangat disegani sekaligus penulis produktif di bidang tafsir, filsafat, sejarah, serta bidang-bidang yang lain. Karyanya yang paling terkenal dan yang paling tebal adalah Tafsir al- Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 42 Mizan. Kemudian juga ada Seyyed Hossein Nasr, guru besar filsafat Islam di Universitas Georgetown, USA yang, hampir semua karyanya sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Iklim keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan pada abad ini, serta adanya kecenderungan Barat untuk mengkaji pelbagai kebudayaan Timur berikut segala aspeknya, secara tidak langsung telah mengarahkan sarjana Barat untuk mengkaji filsafat iluminasi. Menurut Ziai, ada sejumlah tokoh yang secara spesifik bisa dikatakan serius mempelajari aliran filsafat ini. Di antaranya adalah Carra de Vaux yang pada tahun 1902 menulis karangan pendek dalam bahasa Prancis tentang Suhrawardi dengan judul La Philosophie Illuminative d'apres Suhrawerdi Meqtoul. Kemudian Max Horten yang pada tahun 1912 menulis esai-esai pendek tentang Suhrawardi dengan judul Die Philosophie der Erlentung nach Suhrawardi. Lois Massignon yang pada tahun 1929 coba mengelompokkan karya-karya suhrawardi berdasarkan periode tertentu. Otto Spies yang pada tahun 1935 mengedit dan menerjemahkan sejumlah kiasan-kiasan filsafat Suhrawardi yang kemudian disempurnakan oleh WM Thackcson pada tahun 1982 dalam karyanya yang berjudul The Mystical and Visionary Treatises of Shihabuddin Yahya Suhrawardi. Helmut Ritter yang membahas aspek-aspek kehidupan Suhrawardi, serta membedakannya dari tiga mistikus Muslim yang mempunyai nama yang sama—yaitu Abu al-Najib al-Suhrawardi (w. 536 H) dan Abu Hafs Syihabuddin al-Suhrawardi al-Baghdadi (w. 632) penulis kitab Awarif al-Ma'arif—dalam karyanya Philologika IX: Die ver Suhrawardi.. Kemudian pada pertengahan tahun 40-an ada Henry Corbin menyunting Hikmah al-Isyraq dan menulis sejumlah karya tentang filsafat Iluminasi.. (Nasr, 1990, 7-9) Tokoh yang tersebut trakhir di atas nampaknya pantas mendapatkan apresiasi khusus atas intensitasnya dalam mengkaji filsafat iluminasi. Banyak cendekiawan Muslim yang secara terbuka menyampaikan penghargaan terhadanya. Hossein Ziai misalnya, dalam bukunya yang berjudul Suhrawardi & Filsafat Iluminasi menulis: Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 43 Edisi teks Henry Corbin atas karya-karya filsafat Suhrawardi telah mengobarkan perhatian khusus terhadap pemikiran seorang manusia yang secara tradisional dikenal dengan Syaikh al-Isyraq. (Ziai, 1998, 17) Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh Seyyed Hosein Nasr. Menurut Nasr seperti yang dikutip Mehdi Amin Razafi, Corbin adalah sarjana yang telah berbuat banyak bagi pemikiran Suhrawardi. Bahkan, perhatiannya melebihi sarjana Persia sekalipun. (Razafi, 1997, 142) Penghargaan ini nampaknya tidak berlebihan jika menimbang besarnya jasa Corbin yang tidak hanya terbatas pada keseriusannya mengulas naskahnaskah Suhrawardi, namun seperti yang dikutip Drajat juga berhasil mendidik sejumlah sarjana dan figur yang mengikuti jejaknya, baik yang Muslim ataupun yang bukan. Contohnya adalah G. Berger, J. Danielu, G. Durand, A. Feivre, G. Scholem, A. Portmann, dan lain sebagainya. (Drajat, 2005, 73) Lebih lanjut Drajat mengatakan bahwa Oriental Ontology—sebuah buku yang mengulas konsep ontologi Suhrawardi—yang ditulis oleh Corbin berhasil menanamkan pengaruh yang dalam terhadap Young Philosopher (Filsuf Junior). Sekelompok generasi di Perancis yang tokoh terkemukanya bernama Christian Jambet. Bahkan, pengaruh Corbin juga terlihat pada para sarjana Islam-Arab, khususnya yang hidup di negeri bekas koloni Perancis, seperti Al-Jazair. Tokoh besar yang dinilai Drajat banyak terpengaruh Corbin di sini adalah Muhammad Arkoun. (Drajat, 2005, 73) Figur kharismatik yang tak boleh kita lupakan saat membincang perkembangan filsafat iluminasi pada abad ke-20 ini adalah Sir Muhammad Iqbal. Disertasinya yang berjudul The Development of Metaphysics in Persia di bawah bimbingan profesor F. Hammel, tidak hanya membuatnya layak menyandang gelar doktor dari Universitas Munich, Jerman pada tahun 1907, lebih dari itu, disertasi ini harus dipandang sebagai karya yang sukses melukiskan alur pemikiran metafisika di dunia Timur sejak zaman Zoroaster hingga tersimpul secara sempurna di tangan Suhrawardi. Tentang hal ini, Hossein Ziai berkomentar: Penyebutannya dalam halaman demi halaman disertai doktoral Muhammad Iqbal, The Development of Metaphysics in Persia, tetap Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 44 merupakan catatan umum terbaik atas pemikiran filsafat Suhrawardi. (Ziai, 1998, 17) Sebagai catatan penutup, penulis ingin menginformasikan bahwa, perbedaan pandangan dunia Muslim Sunni dan Syiah terhadap pemikiran filsafat telah membawa perlakuan yang berbeda terhadap pemikir muda yang bernama Suhrawardi ini. Pandangan negatif Muslim Sunni terhadap filsafat bukan hanya membuat Suhrawardi berikut semua penerusnya yang penulis uraikan di atas terkesan asing, tapi juga membuat filsafat iluminasi—sama seperti teori-teori filsafat yang lain, sulit mendapatkan tempat. Tapi tidak demikian di kalangan Syiah. Penghargaan mereka yang sangat tinggi terhadap wacana filsafat membuat aliran iluminasi ini tetap hidup dan terpelihara hingga kini. Bahkan, Hikmah alIsyraq—khususnya kajian logikanya—sebagai karya utama Suhrawardi, sampai saat ini masih dijadikan sebagai buku daras di madrasah-madrasah Persia dan sekitarnya. Kitab tersebut diajarkan bersamaan dengan komentarnya yang ditulis oleh Quthbuddin al-Syirazi dan Mulla Sadhra. (Nasr, 1987, 58) Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 BAB 3 LANDASAN PRAEPISTEMIK EPISTEMOLOGI ILUMINASI 3.1. Selayang Pandang Filsafat Iluminasi Apabila ditinjau dari segi linguistik, maka kata iluminasi adalah terjemahan dari kata bahasa Inggris ilumination yang juga ditirunkan dari bahasa latin iluminare dengan makna yang sama, yaitu menerangi. Miskinnya kosa kata dalam bahasa Indonesia membuat kata iluminasi seolah tidak menemukan padanan yang tepat untuk diterjemahkan. Kegigihan para peminat filsafat untuk menerjemahkan kata tersebut ke dalam glosari Indonesia ternyata malah membuatnya kehilangan daya magis dan keunikannya. Kata "filsafat cahaya" atau "filsafat pencerahan" bukan hanya tidak mewakili keutuhan makna kata "filsafat iluminasi" itu sendiri, alih-alih malah membuat maknanya menjadi kabur dan rancu. Nampaknya, para pengkaji filsafat di tanah air harus memosisikan kata ini sama seperti term-term khas lain dalam filsafat yang tak perlu diterjemahkan, seperti "emanasi", "apropriasi", "alienasi", dan lain sebagainya. Kendati kata iluminasi berasal dari bahasa Inggris dan latin, bukan berarti aliran filsafat ini tumbuh dan berkembang di dua wilayah yang menggunakan dua bahasa tersebut. Jadi, meskipun unsur lingistik filsafat ini berasal dari kata Inggris, bukan berarti kita akan menemukan alur sejarah perkembangan pemikiran filsafat ini pada pemikir Inggris, atau bahkan latin. Bahwa benih-benih filsafat ini sudah ada sejak masa Yunani klasik, memang benar dan tak terbantahkan karena ada fakta historis yang menguatkannya. Akan tetapi, juga merupakan fakta historis bahwa kata iluminasi menjadi term yang mengacu pada aliran besar dalam dunia filsafat terjadi ketika Suhrawardi mengemukakan pandangan-pandangan filosofisnya. Menurut Hosesn Ziai, sebelum Suhrawardi mengemukakan teorinya, di belahan dunia Timur sama sekali belum ditemukan teori filsafat iluminasi. (Ziai, 552) Karena teori filsafat ini dibangun di dunia Timur oleh arsitek besar yang berbahasa Arab, berarti untuk mengetahui makna kata filsafat iluminasi berikut segala implikasi filosofisnya, kita harus mengadakan penelitian terhadap glosari bahasa Arab, bahasa yang mendapat kehormatan untuk dijadikan media oleh sang arsitek dalam memaparkan konsep-konsepnya. Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 46 Dalam bahasa Arab, kata iluminasi biasa disebut dengan isyraq. Sebuah kata yang memiliki dua makna yang sangat jauh berbeda namun berkat kecanggihan Suhrawardi berhasil dielaborasi dalam satu struktur yang indah dan terpadu. Makna yang pertama adalah "cahaya" sedangkan makna yang kedua adalah "timur". Jika makna yang pertama mengacu kepada sebuah entitas unik yang dalam dunia fisika modern masih diperdebatkan statusnya apakah merupakan materi atau partikel, maka makna yang kedua mengacu kepada salah satu arah mata angin yang sangat lekat dengan masalah-malasah geografis. Di tangan Suhrawardi, kedua makna yang terkesan diametral ini kemudian ditarik ke dalam wilayah filsafat, lalu dijadikan sebagai simbol utama. Jadi, filsafat iluminasi berkaitan dengan simbolisme matahari yang terbit di timur dan mencahayai segala sesuatu. Karena realitas mencahayai atau menerangi segala sesuatu ini, maka cahaya lantas diidentifikasi dengan gnosis dan iluminasi. Dengan demikian, kata isyaqiyyah bisa dipahami sebagai ketimuran dan iluminasi. Ia memancar karena ia berada di timur, dan ia berada di timur karena ia memancar. Seakan merasa nyaman dengan menggunakan bahan yang bernama geografis, Suhrawardi kemudian merampungkan pondasi bangunan pemikiran filsafatnya dengan menghamparkan garis horizontal simbolik dari "timur" ke "barat" lalu dipadu dengan garis vertikal simbolik dari atas ke bawah sehingga terlihat jelas implikasi cahaya bagi setiap wilayah geografis-simbolik tersebut. Menurutnya, timur adalah belahan dunia yang banyak mendapatkan limpahan cahaya sehingga wilayah ini bebas dari kegelapan dan bebas dari materi. Makanya, belahan dunia ini hanya dihuni oleh entitas-entitas non-materi seperti malaikat. Sedangkan barat karena sedikit menerima limpahan cahaya menjadi gelap sehingga disesaki oleh entitas-entitas materi. Batas yang mengantarai timur dan barat ini disebut "barat-tengah" (middle-occident) yang disimbolkan sebagai wilayah temaram di mana cahaya membaur dengan kegelapan. Wilayah ini ditinggali oleh bintang-bintang tetap (fix stars) yang oleh Seyyed Hossen Nasr disebut sebagai the premium mobile. (Nasr, 1964, 65) Penggunaan simbolisme geografis seperti timur, barat, barat-tengah, serta cahaya seperti ini mungkin oleh Suhrawardi dilakukan untuk mempermudah Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 47 pembacanya memahami konsep metafisika yang sangat abstrak dan sulit untuk dituangkan dalam premis-premis naratif biasa. Sayangnya pada sejumlah kasus, banyak para pembaca karyanya yang malah bingung dengan penggunaan simbolsimbol tersebut, bukan mendapatkan kemudahan. Beruntunglah Seyyed Hossen Nasr—setelah melakukan penelitian yang cermat dan mendalam—berhasil menerangkannya secara gamblang bagi kita. Dalam Three Muslim Sages ia memaparkan bahwa secara kongkret, simbol "barat" mengacu pada wujud bumi yang didominasi oleh unsur materi. "Barat-tengah" mewakili alam astronomis, sementara simbol timur melambangkan alam atas yang berada jauh di balik yang terindra, yaitu alam yang tak terjangkau penglihatan. (Nasr, 1964, 65) Dengan memahami simbolisme geografis ini, akhirnya kita bisa sampai pada kesimpulan bahwa term-term timur, barat, barat-tengah sejatinya tidak mengacu pada wilayah tertentu di muka bumi seperti yang berlaku dalam disiplin ilmu geografi. Tapi semuanya merupakan term khas yang digunakan untuk memetakan seluruh realitas secara holistik. Realitas luhur yang immateri dilambangkan dengan kebercahayaan yang berada di "wilayah timur", sedangkan realitas pekat yang materi dilambangkan dengan kegelapan yang berada di "wilayah barat". Dengan melakukan penafsiran yang euristik terhadap simbolisme cahaya dan kegelapan ini, rasanya tak ada yang menghalangi kita untuk mengatakan bahwa setiap insan yang menginsafi dan mengutamakan dimensi immaterinya, berarti ia telah berada di "wilayah timur" dalam simbiolisme geografis-filosofis Suhrawardi, meskipun secara geografis-empiris ia tinggal di belahan dunia Barat. Sebaliknya, orang yang tidak menyadari jati diri dan hanya memerhatikan dimensi materinya, berarti ia berada di "wilayah barat" dalam simbolisme geografisfilosofis Suhrawardi, walaupun secara geografis-empiris ia tinggal di belahan dunia Timur. Kesimpulan semacam ini bisa diturunkan dari premis bahwa; orang yang mengutamakan dimensi immaterinya, adalah orang yang mengeksplorasi potensi ruhani atau daya kreatif batin yang hanya dimiliki manusia, dan tidak dipunyai oleh entitas apapun yang menghuni kolong langit ini. Sosok seperti inilah yang Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 48 menyadari betul makna dan tujuan hidup di muka bumi. Sosok seperti ini jelas berbeda dengan orang-orang yang hanya terpesona dengan dimensi materi dalam dirinya. Eksploitasi terhadap dimensi "gelap" dalam diri ini sebagian besar—kalau tidak semuanya—hanya tertuju pada pemenuhan hasrat ketubuhan. Sebuah eksploitasi yang juga bisa dilakukan oleh entitas-entitas lain yang bersama-sama manusia turut meramaikan planet yang bernama bumi. Dengan kata lain, filsafat iluminasi ini telah memperkenalkan kita pada satu hal yaitu; untuk memperoleh kebenaran yang beriluminasi dari pencahayaanNya, manusia harus menjadi "cahaya" bagi dirinya sendiri. Caranya adalah dengan menyadari bahwa secara esensial manusia diciptakan sebagai makhluk yang dianugerahi akal dan hati, rasionalitas dan spiritualitas untuk mencapai kodrat kemanusiaan dan kebercahayaan dalam dirinya. Manusia adalah cahaya atau cerminan dari cahaya-Nya. Dengan diri yang bercahaya ini, barulah manusia bisa merengkuh kesejatian insani yang sesungguhnya, menjadi figur pencerah bagi dunia, dan memancarkan pesona yang tak habis-habisnya memberi kedamaian di muka bumi. Puncak dari filsafat ini adalah keterangan dan kejernihan. Karenanya, tak ada yang lebih sentral dari cahaya, sebagaimana tak ada yang lebih urgen dari cahaya. Sebab, meskipun tidak bersifat materi dan tak bisa didefinisikan, cahaya adalah realitas yang meliputi segala sesuatu dan menembus ke dalam struktur setiap entitas, baik fisik maupun non-fisik sebagai sesuatu yang esensial dari entitas itu sendiri. 3.2 Lingkup Bahasan Filsafat Iluminasi Sebagai bangunan filsafat yang besar dan megah, sudah barang tentu Suhrawardi membicarakan banyak masalah yang berkembang pada masanya. Beragam persoalan aktual yang hangat diperbincangkan dalam diskusi-diskusi filsafat, ia uraikan dalam perspektif iluminasi dengan argumentasi yang logis, rasional, dan meyakinkan. Dalam hal ini, konsistensi Suhrawardi dalam mengulas persoalan tersebut dalam bingkai filsafat cahaya rasanya perlu mendapatkan apresiasi yang sepadan. Sebab, bukanlah perkara mudah untuk bisa menerangkan pelbagai tema filosofis dengan tetap berpegang teguh pada unsur metafisika dan Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 49 ontologi. Tidak banyak pemikir yang mampu melakukannya dengan baik. Dan, Suhrawardi adalah satu di antara segelintir pemikir yang mampu melakukannya dengan gemilang. Dalam kajian ini, penulis akan coba memberikan sketsa singkat sejumlah tema besar dalam filsafat ilmunasi yang, menurut hemat penulis, bisa secara perlahan mengantarkan kita pada pembahasan inti tentang tema epistemologi. Karena yang menjadi dasar pertimbangan adalah keterkaitan tema tersebut dengan kajian kita, maka penulis hanya memilih tema-tema tertentu yang memang relevan, dan menyisihkan tema lain yang kurang, atau tidak berkaitan dengan kajian ini. Atas dasar itulah, penulis kemudian memilih tema kosmologi (kajian tentang tema ini sudah penulis lakukan dengan terperinci dalam skripsi yang berjudul: Mayapada di Mata Sang Iluminasionis) dan psikologi serta mengakhirinya dengan ulasan singkat tentang epistemologi. Ketiga tema ini memiliki keterkaitan yang erat jika ditinjau dari sudut pandang tertentu, dan akan membentuk garis linier yang menghubungkan antara sebuah tema yang bersifat universal menuju tema yang bersifat partikular. Pemikiran Suhrawardi yang lain, seperti teorinya tentang Tuhan, visi, intuisi, wujud, dan lain sebagainya sengaja penulis abaikan dengan alasan, tidak memiliki kaitan yang spesifik dengan kajian kita, dan hanya akan membuat karya tulis ini menjadi kurang efektif, walaupun mungkin akan jauh lebih tebal. Jika hukum logika Aristotelian menyaratkan agar suatu silogisme diawali dengan premis mayor yang bersifat universal, maka tak ada alasan untuk dipersalahkan kalau penulis menggunakan hukum yang sama dalam konteks yang berbeda. Karena yang diambil dari logika Aristotelian itu hanya esensi hukumnya saja, maka jangan ditafsirkan bahwa ketiga tema yang sengaja dipilih ini sebagai ketiga premis yang biasa dioperasikan dalam silogisme, meskipun ketiganya memiliki keterkaitan istimewa. Yang ingin penulis sampaikan hanyalah, ketiga tema yang dipilih ini memiliki titik kesamaan dengan ketiga premis dalam silogisme. Tema pertama berfungsi sebagai premis mayor yang berisi keterangan umum, dilanjutkan dengan tema kedua yang berfungsi sebagai premis minor yang berisi keterangan khusus, dan diakhiri dengan tema ketiga yang berfungsi sebagai penjelas kajian ini, bukan sebagai kesimpulan seperti dalam silogisme. Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 50 3.2.1 Kosmologi Masalah pertama yang harus dituntaskan dalam kajian kosmologi tentu saja adalah bagaimana proses terciptanya alam semesta ini. Bagi para filsuf teis— khususnya yang beragama Islam, pertanyaan dasar yang harus dijawab bagaimana cara Tuhan menciptakan alam semesta? Apakah ia tercipta secara spontan sebagai akibat dari kata "Kun" (Jadilah) seperti yang diceritakan al-Quran ketika Tuhan menghendaki sesuatu? Atau, adakah proses lain yang sengaja Dia pergunakan untuk menciptakan alam semesta ini? Supaya kajian ini tetap berada di atas ranah filosofis dan tidak jatuh kepada dogma teistik, marilah kita ikuti pemikiran spekulatif Suhrawardi tentang proses penciptaan alam raya. Menurutnya, Tuhan menciptakan mayapada ini secara iluminatif. Dengan kata lain, secara keseluruhan, alam semesta merupakan sebuah proses penyinaran raksasa, di mana semua entitas yang ada, bermula dari dan bergantung pada Wujud Yang Tunggal atau Nur al-Anwar. Pendapat ini melahirkan 2 konsekuensi logis yang kelihatannya sulit untuk dipecahkan. [1] Jika Tuhan menciptakan alam semesta secara iluminatif, berarti alam sama dengan Tuhan, azali dan abadi. [2] Bagaimana menerangkan keragaman makhluk yang menghuni alam semesta ini, sementara Tuhan sebagai sumber iluminasi bersifat Tunggal? Konsekuensi yang pertama ia hadapi secara konsisten dengan menyatakan bahwa alam semeta memang bersifat azali dan abadi. Sebab, ia berasal dari Tuhan yang ada tanpa awal dan kekal tanpa akhir. Namun ia buru-buru meluruskan bahwa Tuhan dan alam adalah dua entitas yang berbeda. Meskipun alam ini azali dan abadi, bukan berarti ia mandiri laksana Tuhan. Tuhan tetap lebih dahulu dari alam, namun keterdahuluan ini bukan dalam aspek ruang dan waktu, sebab keduanya—ruang dan waktu—ada setelah alam ini ada. Jadi, letak keterdahuluan Tuhan dari alam adalah pada aspek esensi. Dengan kata lain, esensi Tuhan mendahului keberadaan esensi alam. Supaya lebih mudah dipahami, Suhrawardi kemudian mencontohkan hubungan antara lentera dengan cahayanya. Betapa pun cahaya langsung ada begitu lentera menyala, dan akan tetap ada sepanjang ada lentera, kita pasti dengan mudah mengatakan bahwa secara esensial, keberadaan Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 51 lentera lebih dahulu dari cahaya, karena lenteralah yang berfungsi sebagai kausa prima yang menghasilkan cahaya. . ﻓﯿﺪوم اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺪواﻣﮫ، إذ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻻ ﯾﺘﻐﯿﺮ وﻻ ﯾﻨﻌﺪم،واﻟﻔﯿﺾ أﺑﺪي "أن "اﻟﻔﯿﺾ ﻟﻮ دام ﻟﺴﺎوى ﻣﺒﺪﻋﮫ ,اﻟﺸﻌﺎع . . ﺑﻞ ھﻮ ﻣﻨﮫ وﺑﮫ،ﯾﻮﺟﺒﮫ Emanasi adalah proses yang abadi, karena subjeknya tidak pernah berubah atau tiada. Dan karenanya, alam semesta abadi dengan keabadian-Nya. Pernyataan yang menerangkan, "Andaikan emanasi itu abadi, ia akan menyamai penciptanya," tidak dapat dibenarkan. Karena Cahaya yang Mahamenyala selalu mendahului sinar, sekalipun keberadaan sinar menjadi petunjuk ke arah eksistensi Cahaya yang mengada sebelum eksistensi dan ketakberadaannya, atau sebelum ketakberadaan yang memungkinkannya bereksistensi sesudahnya. Esensi yang terimplikasi eksistensinya, tidak setara dengan Esensi yang mengimplikasi; ia mengada dari dan dengan eksistensi-Nya. (Suhrawardi, 1993, 181) Sukses memberikan argumentasi berikut analogi yang memuskan untuk menjawab konsekunsi yang pertama, Suhrawardi dengan hati-hati berusaha menjawab konsenkuensi berikutnya dengan menyatakan bahwa, Tuhan memang bersifat Esa dan menguasai seluruh cahaya. Dia merupakan Entitas Esa yang meliputi segala sesuatu, baik yang fisik maupun yang non-fisik. Sebagai Zat Yang Mahaesa Tuhan memancarkan cahaya pertama yang disebut Nur al-Aqrab. Proses kemunculan Nur al-Aqrab dari Nur al-Anwar (Tuhan) tidak dengan cara memisah atau membelah diri. Sebab, pemisahan dan pembelahan—menurutnya—mengindikasikan adanya dualitas. Untuk menyederhanakan ilustrasi proses lahirnya Nur al-Aqrab dari Nur al-Anwar ini, Suhrawardî mengumpamakannya dengan matahari berikut cahaya yang dihasilkannya. (Suhrawardi, 1993, 137-138) Ilustrasi ini hanya mendekati dan hanya ditujukan untuk mempermudah pemahaman, mengingat proses iluminasi yang sesungguhnya sangat abstrak dan sulit dipahami. Dari Nur al-Aqrab inilah awal keragaman dimulai. Menurut Suhrawardi, ada dua keragaman yang menjadi cikal keberagaman tak terhingga selanjutnya yang muncul dari Nur al-Aqrab. [1] Ditinjau dari sifatnya, Nur al-Aqrab ini memiliki dua sifat. Bagi dirinya ia bersifat mumkin al-wujud (bisa ada), Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 52 sedangkan bagi cahaya di bawahnya ia bersifat wajib al-wujud (niscaya ada). [2] Ditinjau dari sisi yang lain, Nur al-Aqrab ini tidak hanya melahirkan cahaya, tapi juga barzakh (mohon dipahami dalam konteks filsafat iluminasi) sebagai substansi yang mengantarai antara dirinya dengan cahaya di bawahnya. Barzakh ini akan terus muncul dan menjadi pengantara antara cahaya yang di atas dengan cahaya yang di bawahnya. Dengan demikian, Suhrawardi sudah mendapatkan peluang besar untuk menerangkan alur keragaman yang terjadi di alam semesta. Proses penyinaran selanjutnya adalah tiap tingkatan cahaya meneruskan cahaya yang dimilikinya kepada cahaya yang ada di bawahnya. Setiap tingkatan cahaya juga menerima satu kali pancaran dari Nur al-Anwar. Karena setiap tingkatan menerima pancaran cahaya dari tingkatan di atasnya sebanyak yang dimiliki, dan ditambah satu kali pancaran dari Nur al-Anwar, otomatis, semakin rendah tingkatan cahaya, semakin banyak pancaran yang dimiliki, namun semakin rendah intensitasnya. Semakin rendah intensitas cahaya, semakin berkurang juga dimensi immaterinya, dan semakin pekat dimensi materinya. Peluang untuk menerangkan proses keragaman ini dimanfaatkan dengan sempurna oleh Suhrawardi dengan menyatakan bahwa, proses penyinaran tersebut tidak hanya bersifat rasional—bukan temporal, tapi juga tidak hanya membentuk garis lurus ke bawah secara vertikal, tapi juga menghasilkan cahaya yang memanjang membentuk garis horizontal. . . . . ﻣﺎ ﺣﺼﻠﺖ أﻧﻮاع ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ، وﻟﻮﻻ ذﻟﻚ.ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ "Hendaknya diketahui bahwa fenomena hierarkis al-Anwar al-Qahirah yang satu dengan yang lain bersifat rasional, bukan temporal. al-Anwar alQahirah ini tidak akan mampu dihitung dan dipastikan oleh umat manusia. Cahaya ini juga tidak hanya memanjang secara vertikal semata, akan tetapi juga berimbang (secara horizontal). Ini dikarenakan modalitas-modalitas kebercahayaan Cahaya Tinggi yang plural atau persekutuan antara yang satu dengan yang lain memungkinkan lahirnya al-Anwar al-Qahirah alMutakafi'ah. Sebab, tanpa mereka tidak akan muncul genus-genus yang berimbang." (Suhrawardi, 1993, 178) Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 53 Hierarki memanjang ke samping (hierarki horizontal) ini memiliki sistem yang berbeda dengan hirarki vertikal seperti diterangkan di atas. An-Anwar alQahirah vertikal ini merupakan hasil tidak langsung dari hierarki vertikal dalam struktur piramida iluminasi. Derajat cahaya dalam hierarki ini setara dan bersifat plural. Suhrawardî menyebutnya dengan al-Anwar al-Mutakafiah atau Arbab alAshnam, (Suhrawardi, 1993, 178) yang artinya adalah cahaya-cahaya ini merupakan pelindung dari genus-genus yang ada di alam nyata. Dengan kata lain, segala sesuatu yang ada di dunia ini, memiliki kembaran di alam malakut. Setelah sukses menerangkan proses terjadinya keragaman di alam semesta, berarti satu-satunya masalah yang tersisa adalah menjelaskan proses metamorfosa dari cahaya yang immateri sehingga tercipta materi di alam semesta ini. Bagi Suhrawardi, masalah ini tidaklah sulit untuk dipecahkan. Seperti diterangkan di atas bahwa semakin rendah tingkatan cahaya, semakin banyak pancaran yang dimiliki namun semakin rendah intensitasnya, demikian jugalah proses terciptanya materi. Artinya, materi tercipta karena semakin jauh cahaya dari Tuhan, semakin kecil intensitas dan kemurniannya, dan semakin minim pula unsur imaterinya, sehingga lama kelamaan, semakin jauh suatu cahaya dari Tuhan, semakin dominan unsur materialnya, sehingga pada titik tertentu itulah, lahirlah benda-benda materi seperti yang berserak di alam semesta. Terakhir, Suhrawardi menyatakan bahwa berdasarkan refleksi filosofisnya, ada 4 alam yang menyusun sistem kosmologi. [1] Cahaya Dominator yang oleh Suhrawardi disebut al-Anwar al-Qahirah. Ini merupakan alam cahaya murni yang rasional dan benar-benar terbebas dari unsur materi. Menurut al-Syahrazuri dalam catatan kaki Hikmah al-Isyraq, alam ini dihuni oleh tentara Tuhan yang terdiri dari para malaikat yang dekat dengan-Nya dan hamba-Nya yang luhur. [2] Cahaya Pengatur yang ia sebut al-Anwar al-Mudabbirah. Ini adalah alam cahaya bintangbintang dan kemanusiaan. [3] Dua Barzakh yang ia sebut Barzakhan. Barzkah pertama adalah alam materi yang berisi data-data indrawi. Sedangkan barzakh kedua barzakh kosmik yang berisi bintang-bintang dan unsur-unsur elementer yang memuat esensi-esensi terstruktur. [4] Citra dan Imajiner yang ia sebut sebagai al-Asybah al-Mujarradah. Di alam inilah, proses pembangkitan jasmani Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 54 berikut semua balasan yang dijanjikan dalam risalah kenabian akan terlaksana. (Suhrawardi, 1993, 232-235) 3.2.2 Psikologi Setelah memahami teori kosmologi iluminasi yang dalam kajian ini kita posisikan sebagai "premis mayor", mari kita persempit kajian ini dengan mengambil manusia sebagai satu di antara sekian banyak entitas penghuni alam semesta dan kita jadikan sebagai "premis minor". Penulis yakin, kajian tentang manusia bisa menjadi "premis minor" karena dalam ralitas keseharian, pencitraan manusia sebagai mikrokosmos, miniatur yang mewakili pruralitas alam semesta sebagai makrokosmos sudah bukan istilah yang baru. Sayangnya, penulis tidak bisa menyajikan pembahasan tentang filsafat manusia secara utuh, namun hanya akan mengambil salah satu unsur penting sekaligus yang membuatnya sebagai makhluk unik dan istimewa, yaitu unsur kejiwaaannya saja. Dengan kata lain, pasal ini hanya akan mengupas teori iluminasi tentang jiwa atau psikologi. Alasan lain mengapa penulis hanya mengupas masalah psikologi ini adalah, karena masalah ini berkaitan secara signifikan dengan masalah epistemologi. Bahkan bisa dikatakan kalau Suhrawardi membangun konsep epistemologinya atas dasar psiklogi. Jadi, masalah jiwa dan mental ini memainkan peranan penting yang harus betul-betul dipahami dalam teori Suhrawardi tentang ilmu pengetahuan. Secara runtut, uraian tentang jiwa dalam Hayakil al-Nur, dimulai dengan pembuktian keberadaannya. Baginya, bukti paling sahih atas keberadaan jiwa adalah fakta bahwa manusia sepanjang waktu tidak pernah lupa dan alpa tentang esensinya, tentang jati dirinya. Pada waktu-waktu tertentu, manusia boleh saja lupa akan organ fisiknya, tapi tak ada jeda di mana manusia lupa akan kediriannya. Itulah sebabnya, mengapa esensi manusia sejatinya bersifat spiritual, bukan material. Jadi, tegas Suhrawardi, ketika manusia berkata "Aku," identitas yang ditunjuk sebenarnya jauh lebih tinggi daripada setiap wujud material manusia. (Suhrawardi, 2003, 51) Sesuai dengan prinsip iluminasi, Suhrawardi meyakini jiwa manusia itu adalah cahaya suci yang kekal, selalu hidup, tetap, tak dapat dibagi atau dianalisa. Hal ini terjadi karena jiwa berasal dari Tuhan Yang Mahakekal dan Mahamutlak. Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 55 Dengan tegas Suhrawardi mendefiniskkan jiwa sebagai salah satu cahaya Tuhan yang tidak memiliki dimensi dan tidak bertempat. Ia terbebas dari ruang dan waktu. Ia bukan bagian dari dunia ini dan juga bukan bagian dari selainnya. Ia tidak bergantung kepada dunia tapi juga tidak terbebas darinya. Ia terbit dari Tuhan dan akan terbenam di dalam-Nya. Jiwa adalah misteri tak terungkap dalam hadis qudsi yang berbunyi, "Aku adalah perbendaharaan tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka Kuciptakan makhluk." (Suhrawardi, 2003, 54-55) Dari definisi yang sangat ideal sekaligus abstrak ini, sangat sulit bagi kita untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang jiwa seperti yang dikonsepsikan oleh Suhrawardi. Yang bisa kita lakukan mungkin hanyalah memberikan penilaian bahwa, Suhrawardi sejatinya ingin menarik garis demarkasi yang tegas antara dimensi materi manusia yang diwakili oleh jasad kasar yang fana dan senantiasa berubah, dengan dimensi immateri yang halus dan tak dapat dicandra. Apabila mengamati garis demarkasi ini, kemudian menelaah paparanpaparan Suhrawardi selanjutnya, akan terlihat bahwa filsuf iluminasi ini nampkanya lebih cenderung berpandangan spriritualis-idealis walaupun tidak terlalu ekstrem. Penulis berani melakukan justivikasi semacam ini karena Suhrawardi tidak ragu untuk mengacu dimensi immateri (baca: jiwa) di balik kata "Aku" yang diucapkan oleh seseorang. Ia tidak memberikan porsi yang berimbang antara dimensi jiwa dan dimensi raga di balik kata tersebut. Esensi, seorang "aku" dalam pernyataan Anda tentang "aku" adalah sesuatu yang tak dapat dibagi, tetap, dan kekal. Oleh karena itu, esensi Anda bersifat non-material, dan tidak mungkin merupakan bagian dari wujud material. (Suhrawardi, 2003, 52) Sesudah menyatakan jiwa bersifat kekal, Suhrawardi dengan segera menyatakan bahwa kekekalan jiwa berbeda dari kekekalan Tuhan. Menurutnya, orang yang mengatakan jiwa manusia kekal dan mandiri layaknya Tuhan, takkan bisa menjawab pertanyaan "Siapa yang memisahkan jiwa dari tempat sucinya, lalu memasukkannya ke dalam alam kehidupan ini, lalu mengambilnya dari dunia ini untuk dibawa ke alam kematian dan kegelapan?" Ingat, seorang bayi yang baru lahir tidak memiliki daya untuk menarik jiwa dari alam cahaya, alam kesucian. Hanya Tuhanlah yang memindahkan jiwa itu dari alam kesucian ke dalam jasad manusia, katika jasad tersebut sudah memiliki potensi untuk menerimanya. Dan, Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 56 Dia jugalah yang akan memindahkannya kembali dari tubuh manusia menuju alam cahaya. Tentang hal ini ia menulis: Seperti Anda ketahui, api dari sebuah korek api tidak kehilangan apa pun ketika menyulut sesuatu yang mudah terbakar. Jiwa akan masuk ke dalam jasad, jika jasad mempunyai potensi untuk menerimanya, tanpa menyebabkan kekurangan kepada Yang Memindahkan jiwa kepada jasad itu. (Suhrawardi, 2003, 61) Walaupun diciptakan dan berasal dari Zat Yang Tunggal, bukan berarti jiwa manusia itu tunggal. Menurut Suhrawardi, jiwa sama dengan jasad, ia bersifat majemuk dan berbeda antara yang satu dengan yang lain. Alasannya, jika jiwa yang dimiliki manusia tunggal dan sama, praktis, sesuatu yang diketahui seseorang juga pasti diketahui oleh orang lain. Tapi tidaklah demikian faktanya. Jelasnya, sebagaimana Tuhan mengiluminasikan jasad yang berbeda-beda terhadap manusia, Dia juga mengiluminasikan jiwa yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Dengan kata lain, kuantitas dan tingkat kemajemukan jiwa berbanding lurus dengan kuantitas dan jumlah manusia. Jadi, setiap manusia hanya memiliki satu jiwa yang aktif dan menjadi daya bagi dirinya sendiri. Sebagai daya hidup yang mengatur tubuh manusia, menurut Suhrawardi, jiwa memiliki daya lahir dan daya batin. Daya lahirnya tercermin dari pancaindra yang bisa diketahui secara empiris melalui indra peraba, perasa, pencium, pendengar, dan penglihat. Sedangkan daya batinnya adalah: [1] Daya Imajinasi. Ini adalah daya yang berfungsi mengabadikan kesan-kesan yang ditangkap oleh indra luar. [2] Daya Pikir. Ini adalah daya yang berfungsi menganalisa, menyusun, menyeleksi, mengafirmasi, serta menyimpulkan kesan-kesan yang masuk. [3] Daya Estimasi. Ini adalah daya yang membawa pada khayalan dan ilusi yang dalam cara kerjanya seringkali bertentangan dengan daya pikir. Suhrawardi mencontohkan rasa takut yang merayap ke dalam hati saat seseorang dibiarkan bersama jenazah. Daya akal pasti membuat seseorang tenang, karena secara faktual orang yang sudah mati memang tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang yang masih hidup. Sayangnya, daya estimasi memainkan tipu dayanya terutama berkaitan dengan hal-hal yang tidak dapat dicerap dengan jelas oleh indra. [4] Daya Memori. Ini adalah daya yang menyimpan dan mengingat semua yang telah terjadi. (Suhrawardi, 2003, 55-57) Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 57 Semua daya ini, lanjut Suhrawardi, mengambil tempat tertentu dalam otak yang saling terpisah antara yang satu dengan yang lain. Sehingga, ketika terjadi gangguan pada salah satu tempat di mana suatu daya berada, gangguan itu hanya merusak daya yang berada di tempat tersebut, sementara daya yang berada di tempat atau bagian lain dalam otak, tetap aman, tidak terpengaruh, dan bisa menjalankan fungsinya dengan baik. (Suhrawardi, 2003, 57) Pada titik ini pun kita akan kesulitan menghayalkan di mana posisi persis suatu daya mengambil tempatnya dalam otak, atau bahkan, apakah otak yang dimaksud oleh Suhrawardi adalah otak dalam pengertian empiris yang bertempat di balik tengkorak kepala, atau bukan. Kita tidak bisa secara lugas memastikan bahwa otak yang dimaksud Suhrawardi adalah otak dalam pengertian yang empiris. Mengapa? Karena di muka penulis sudah mengutipkan pernyataan Suhrawardi yang menegaskan bahwa jiwa merupakan dimensi immateri yang tidak menempati dimensi ruang dan waktu sehingga tidak bisa dikuantivisir dan dianalisa. Beralih dari polemik rumit yang sulit untuk diselesaikan ini, marilah kita ambil salah satu uraian yang secara langsung bisa mengantarkan kita pada tema selanjutnya, yaitu tema epistemologi. Uraian itu terletak pada pembagian daya yang dimiliki jiwa, yaitu dan daya lahir dengan kelima pancaindranya dan daya batin dengan keempat potensinya. Sebab, kedua daya inilah yang memiliki premis-premis khusus yang berkaitan dengan konsep ilmu pengetahuan. Di samping itu, kedua daya itu jugalah yang berperan besar dalam semua tindak mengetahui manusia. 3.2.3 Epistemologi Konsep epistemologi dalam filsafat iluminasi lazim disebut ilmu hudhuri. Ini adalah terminologi khas yang hanya ada dalam filsafat iluminasi. Oleh sebab itulah, penulis secara bergantian menggunakan istilah ini—epistemologi iluminasi atau ilmu hudhuri—karena mengacu pada modus ilmu pengetahuan yang hanya digagas oleh Suhrawardi. Penulis sama sekali tidak khawatir kedua istilah tersebut dipahami secara berbeda karena dua alasan. Pertama, konsep ilmu hudhuri hanya ada dalam filsafat iluminasi dan tidak dijumpai dalam aliran filsafat lain. Walaupun mungkin ada dalam sistem filsafat lain, tidak ada penamaan yang spesifik sebaga ilmu hudhuri seperti yang Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 58 dilakukan oleh Suhrawardi. Dengan kata lain, tokoh yang pertama dan paling berhak menggunakan istilah ilmu hudhuri adalah Suhrawardi sang pencetus filsafat iluminasi. Para pemikir setelahnya yang juga membahas modus pengetahuan jenis ini, tak lebih dari sekadar memperluas atau menambahkan unsur-unsur tertentu dalam spesies pengetahuan tersebut. Kedua, kajian ini secara spesifik mencantumkan nama Suhrawardi, dengan begitu berarti konsep epistemologi dalam kajian ini hanya mengacu kepada teori yang ia paparkan, tidak mengacu kepada tokoh selain dirinya yang juga mengembangkan konsep epistemologi yang sama. Katakan misalnya Mulla Shadra. Walaupun filsuf yang memiliki nama asli Shadruddin al-Syirazi ini juga menganut aliran iluminasi dan membicarakan ilmu hudhuri, akan tetapi, dalam kajian ini setiap kali di dikutip atau disinggung, penulis pasti menyebutkan namanya. Dengan begitu, pembaca takkan pernah merasa rancu sedang menelaah konsep siapa. Selain Mulla Shadra. Nasiruddin al-Thusi juga tercatat sebagai eksponen utama ilmu hudhuri. Prestasinya dalam epistemologi ini terletak pada uraiannya tentang pengetahuan Tuhan mengenai diri-Nya sendiri dan pengetahuan-Nya mengenai alam semesta. Dalam komentarnya terhadap Ibnu Sina, kepedulian Thusi yang utama adalah menjawab pertanyaan, "Bagaimanakah Tuhan sebagai Wujud Niscaya yang juga bersifat niscaya dalam tindakan pengetahuan-Nya, mengetahui emanasi-Nya?" Dalam kajian ini, penulis sengaja tidak menyinggung Thusi sama sekali karena teori ilmu hudhuri yang ia utarakan terlalu jauh dan sulit dipahami. Teori tentang epistemologi ini merupakan teori yang paling banyak dibicarakan Suhrawardi dalam karya-karyanya, berbeda dengan teori-teori lain seperti kosmologi atau psikologi—seperti penulis contohkan di atas. Dalam Hikmah al-Isyraq, spesies pengetahuan ini hampir selalu dikaitkan dengan konsep epistemologi dalam filsafat peripatetik yang sangat populer pada masa Suhrawardi. Namun penulis sengaja tidak mengupas teori epistemologi aliran tersebut kecuali sangat diperlukan. Jadi, penulis berusaha memilah dan memaparkan epistemologi iluminasi seperti yang digagas Suhrawardi, tanpa harus disandingkan dengan epistemologi peripatetik. Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 59 Menurut Yazdi, ajaran Suhrawardi tentang spesies pengetahuan ini ditandai oleh ciri intrinsik "swaobjektivitas", baik dalam mistisisme maupn dalam manifestasi lain dari pengetahuan ini. Alasannya, sifat esensial pengetahuan ini adalah bahwa realitas kesadaran dan realitas yang disadari oleh diri secara eksistensial adalah satu dan sama. Dengan mengambil hipotesis kesadaran diri sebagai contoh, Suhrawardi mengemukakan bahwa diri haruslah sepenuhnya sadar akan dirinya tanpa perantaraan representasi. (Yazdi, 200369) Analisis Yazdi barangkali didasarkan pada tulisan Suhrawardi yang menceritakan proses "penemuan" ilmu hudhuri. Sebuah proses yang tidak hanya unik, tapi pada batasan-batasan tertentu bisa dikatakan sebagai kurang logis, dan menyimpang dari proses penemuan spesies ilmu pengetahuan jenis lain. Betapa tidak, Suhrawardi secara jelas menyatakan bahwa setelah sekian lama dirundung kerisauan intelektual seputar masalah ilmu pengetahuan, ia akhirnya mendapatkan jawaban memuaskan dalam dialog imajiner dengan Aristoteles yang ia lakukan dalam keadaan tertentu yang sangat sulit, bahkan sekalipun untuk dikhayalkan. Suhrawardi menyebut keadaan itu sebagai Syibh al-Naum. Yazdi menerjemahkannya sebagai trance mistic. Sedangkan Ziai menyebutnya dengan dream vision. Secara literal, kata Syibh al-Naum mungkin bisa diterjemahkan— bukan diartikan—dengan "Setengah Sadar". Dalam al-Talwihat pasal ke-55 yang berjudul Hikayah wa Manam (Kisah dan Tidur), Suhrawardi menghabiskan beberapa halaman untuk mengisahkan pertemuan dan dialog imajinernya dengan Aristoteles. Dalam dialog tersebut, Suhrawardi mengemukakan sejumlah pertanyaan tentang masalah epistemologi, di antaranya, apakah pengetahuan sejati itu? Bagaimanakah cara memerolehnya? Apa yang dikandungnya? Dan, bagaimana ia dinilai? Menjawab ragam pertanyaan ini, Aristoteles menjawab, "Kembalilah kepada dirimu sendiri. Jika itu kau lakukan, engkau pasti menemukan jawaban yang benar bagi pertanyaanmu." (Suhrawardi, 1993, 70). Atas dasar inilah Suhrawardi kemudian membangun suatu pemikiran tentang ilmu pengetahuan yang dilandaskan pada pengetahuan diri, kesadaran diri. Meskipun akar ilmu hudhuri diperoleh dalam suatu dialog imajier yang dilaksanakan dalam keadaan setengah sadar, bukan berarti modus pengetahuan ini Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 60 hanya bisa dioperasikan dalam keadaan persis seperti ketika Suhrawardi mendapatkannya. Tidak, sama sekali tidak. Ilmu hudhuri didasarkan sepenuhnya pada dimensi pengetahuan manusia yang identik dengan status ontologis wujud manusia itu sendiri. Suhrawardi pada dasarnya tetap berusaha memberi landasan kesadaran intelektual kita maupun pengalaman keindraan kita dengan analisis filosofis yang mendalam. Memang, istilah "kehadiran" atau "kesadaran dengan kehadiran" bisa kita temui juga dalam karya-karya Plotinus, dan juga paparanpaparan filosofis Neoplatonis lainnya. Meskipun demikian, pertanyaan, mengapa bentuk kesadaran ini harus menempati posisi pertama dalam realitas diri individual, merupakan suatu masalah yang tidak secara tuntas diulas dalam batang tubuh filsafat Neoplatonis 3.3. Klasifikasi Ilmu Sepanjang melakukan kajian terhadap teori ilmu pengetahuan dalam filsafat iluminasi, ada dua fenomena menarik yang penulis dapatkan dan layak untuk diluruskan. Pertama, banyak sarjana modern yang mengulas masalah ini seolah terjebak dalam salah satu aspek ilmu pengetahuan dalam filsafat iluminasi saja, dan terkesan acuh pada aspek yang lain. Perhatian mereka seolah tersita oleh terminologi ilmu hudhuri yang dikemukakan oleh Suhrawardi. Terminologi ini ibarat magnet yang memiliki kekuatan dahsyat sehigga bisa menarik minat para pengkaji terpusat kepadanya. Penulis tidak menyalahkan ketertarikan mereka, mengingat teori ilmu pengetahuan yang disebut dengan ilmu hudhuri itu memang unik dan mencirikan originalitas pemikiran Suhrawardi, sekaligus memiliki sejumlah perbedaan dengan epistemologi yang lain. Hossein Ziai misalnya, ketika menuliskan hasil penelitiannya terhadap pemikiran Suhrawardi, ia menghabiskan hampir sebagian besar halaman bukunya untuk menguraikan masalah-masalah yang berkaitan dengan aspek intuitif dalam bangunan filsafat Suhrawardi, sehingga nyaris tak ada halaman yang tersisa untuk menjelaskan aspek yang empiris. Fenomena yang sama juga dilakukan oleh Amroeni Drajat saat ia mengulas konsep cahaya dalam filsafat iluminasi. Sangat kentara sekali betapa ia berusaha mati-matian untuk menjelaskan pelbagai istilah tak konvensional yang Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 61 digunakan Suhrawardi dalam bangunan filsafatnya. Seperti menerangkan bahwa konsep anggelologi yang kental aroma Zoroaster tidak bisa dijadikan alasan untuk menganggap Suhrawardi telah kafir, atau menilainya telah berusaha menghidupkan kembali tradisi agama-agama Persia kuno agar bisa berdampingan dengan Islam. Hal yang serupa juga terjadi pada Asmuni ketika ia menulis disertasi tentang konsep kesatuan mistik dalam filsafat iluminasi. Walaupun konsep kesatuan mistik ini berada dalam wilayah ontologi dan metafisika, tapi menurut hemat penulis, tidak adil jika dalam menguraikan konsep itu, kita kemudian terjebak dalam argumen-argumen religius yang sarat dengan nilai-nilai yang harus diterima secara langsung karena bersumber pada teks-teks suci. Teknik penguraian seperti ini, di satu sisi memang mumpuni untuk memberikan legitimasi logis bagi pemikiran filosofis yang sampai sekarang banyak ditolak oleh kalangan masyarakat Islam. Namun di sisi lain, sangat potensial untuk memenjarakan pemikiran filsafat Suhrawardi dalam busana kaegamaan yang hanya bisa dinikmati oleh umat Islam. Padahal dalam beberapa bagian dalam bukunya, Suhrawardi menegaskan bahwa teori-teori yang ia paparkan bersifat universal dan perenial. Dan, kebenaran semacam ini, menurutnya, bersifat abadi serta memiliki juru bicara sepanjang masa. Ia kemudian mencontohkan Plato, Aristotels, Hermes, Empedokles, Phytagoras, Aghasademon, Ascleptus, masih banyak yang lain sebagai juru bicara di belahan Barat, sedangkan Jamasf, Zarathustra, Buzurjumhr, Zoroaster, dan lainlain sebagai juru bicara di belahan Timur. Menurut Suhrawardi, semua juru bicara tersebut hakikatnya menyampaikan kebenaran yang sama, perbedaannya hanya terletak pada cara meredaksikan pesan-pesan kebenaran itu sendiri. Uraian yang berat sebelah yang dicirikan dengan besarnya porsi bagi dimensi mistik-intuitif ini berakibat pada lahirnya fenomena yang kedua. Yaitu mengkristalnya pandangan bahwa Suhrawardi lebih sebagai mistikus daripada seorang filsuf. Kristalisasi pandangan inilah yang kemudian, seperti disinggung di muka, membuat sejumlah pengkaji merasa kurang tertarik pada pemikiran Suhrawardi karena menganggapnya sebagai ungkapan-ungkapan imaginatifspirirual yang bersifat subjektif dan hampir mustahil diterangkan secara filosofis. Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 62 Kedua fenomena inilah yang harus kita luruskan karena memang tidak mencerminkan pemikiran Suhrawardi yang sebenarnya. Karena bagi penulis, Suhrawardi tidak berbeda dengan para filsuf besar lain dalam menguraikan pandangan-pandangan filosofisnya. Bahkan pada titik-titik tertentu, ia lebih cerdas dan pandangannya lebih maju dibandingkan para pemikir yang hidup jauh setelahnya. Dengan kata lain, Suhrawardi tidak semata-mata menggunakan instrumen intuitif dalam membangun pemikiran filsafatnya secara umum, dan menggagas konsep epistemologinya secara khusus. Akan tetapi, ia juga menggunakan instrumen empiris dengan data-data indrawi atau objek-objek fisik yang bisa diindra. Bahkan kalau mau teliti, kita akan mendapatkan bahwa Suhrawardi sejatinya mengombinasikan kedua instrumen itu secara selaras dan indah dalam stuktur bangunan filsafatnya. Sebagai misal, untuk memudahkan pembacanya dalam memahami konsep ilmu hudhuri yang diperoleh melalui kesadaran dan bukan melalui representasi objek, Suhrawardi dengan lincah berhasil mengolah pengalaman eksistensial manusia akan rasa sakit—yang bersifat mental, yang ditimbulkan oleh pelbagai faktor, dan salah satunya adalah karena cedera—yang bersifat empiris. Dalam alMaysari' wa al-Mutharahat dia menulis: ﺤ إن اﻹﻧﺴﺎن ﯾﺘ،اﻟﻤﺪرك ،ﺑﺄن ﺗﻔﺮﯾﻖ اﻹﺗﺼﺎل ﯾﺤﺼﻞ ﻟﮫ ﺻﻮرة أﺧﺮى ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﻀﻮ أو ﻓﻲ ﻏﯿﺮه ﻰ . .ﺣﺼﻮل ذاﺗﮭﺎ ﻟﻠﻨﻔﺲ أو ﻷﻣﺮ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺣﻀﻮري ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ Salah satu yang menguatkan pendapat kami bahwa kita mempunyai kesadaran yang tidak memerlukan representasi selain dari kehadiran realitas sesuatu yang disadari adalah, saat seseorang merasa sakit karena teriris atau mengalami kerusakan pada organ tubuhnya. Saat itu, ia mempunyai perasaan tentang kerusakan ini, namun perasaan atau kesadaran ini tidak pernah terjadi dengan cara yang sedemikian rupa hingga kerusakan itu meninggalkan bentuk representasi dirinya dalam organ tubuh yang sama atau dalam organ lain di samping realitas dirinya. Yang disadari hanyalah kerusakan itu sendiri. Inilah yang benar-benar bisa diindra dan bertanggung jawab atas rasa sakit itu, bukan representasinya, yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Ini membuktikan bahwa, di antara Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 63 hal-hal yang kita sadari, ada beberapa hal yang cukup disadari dengan menerima realitasnya dalam pikiran atau dalam agen yang hadir dalam pikiran. (Suhrawardi, 1993, 485) Berdasarkan kutipan singkat ini, kita bisa mengembangkan dua analisa atau penilaian yang akan bergerak pada dua sisi yang berbeda. Pertama, dengan memusatkan perhatian pada rangkaian-rangkaian kalimat pembuka dan tidak dikecohkan oleh contoh empiris dalam rangkaian kalimat-kalimat berikutnya, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa Suhrawardi telah menggunakan perumpamaan yang bersifat empiris—yaitu rasa sakit pada luka, untuk menerangkan teorinya yang bersifat non-empiris—yaitu ilmu hudhuri. Sejenis pengetahuan yang hanya diperoleh melalui kesadaran. Kedua, dengan menganalisa pengalaman empiris tentang rasa sakit, Suhrawardi sejatinya ingin mengajukan pertanyaan: Apa yang sebenarnya membuat kita menderita ketika mengalami rasa sakit karena luka pada bagian tubuh kita—tangan misalnya—atau dalam bahasanya sendiri, karena representasi dari luka itu? Dalam rangkaian kalimat "Saat itu, ia mempunyai perasaan tentang kerusakan ini, namun perasaan atau kesadaran ini tidak pernah terjadi dengan cara yang sedemikian rupa hingga kerusakan itu meninggalkan bentuk representasi dirinya dalam organ tubuh yang sama atau dalam organ lain di samping realitas dirinya. Yang disadari hanyalah kerusakan itu sendiri. Inilah yang benar-benar bisa diindra dan bertanggung jawab atas rasa sakit itu, bukan representasinya, yang disebabkan oleh dirinya sendiri," Suhrawardi seolah ingin mengatakan bahwa, adalah absurd untuk melemparkan kesalahan pada data indrawi atau representasi dan kemunculan pengalaman rasa sakit, sementara realitas rasa sakit mutlak hadir dalam pikiran yang menderita, yang semuanya hadir dalam pikiran itu. Dengan kata lain, adalah kenyataan fisiologis bahwa perasaan seseorang akan luka pada tangannya, tak lain adalah pengenalannya dengan luka pada tangan itu sendiri, bukan dengan representasi atau data indrawi tentang luka tersebut. Sebuah luka pada tangan kita jelas tidak sama dengan goresan pada meja yang sedang saya kita dan kita sentuh. Dalam pengalaman yang tentang meja, bisa Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 64 dipahami jika dikatakan bahwa di depan meja kita, kita memperoleh data indrawi yang membentuk penampakan meja kita, baik warnanya atau bentuknya. Akan tetapi, dalam "kehadiran" realitas suatu luka pada tangan, hampir tidak ada artinya mengatakan bahwa kita berkenalan dengan data indrawi yang membentuk penampakan tangan kita yang luka, warnanya, bentuknya, bengkaknya, dan lain sebagainya. Apakah semua ini benar-benar menjelaskan rasa sakit kita? Tidak sama sekali! Memang, kita bisa melihat dan menyentuh tangan kita yang terluka dari luar dan mengenal data indrawi yang membentuk penampakan luka pada tangan kita, seperti yang dilakukan oleh dokter, tetapi pengenalan semacam ini tak sama dengan pengenalan kita dengan rasa sakit itu sendiri. Jelasnya, pengenalan kita terhadap rasa sakit itu benar-benar berbeda dengan pengenalan kita terhadap luka yang ada pada tangan kita. Kalau pengenalan kita terhadap luka di tangan itu bisa dilakukan oleh indra, lantas, bagaimana kita mengenal rasa sakit yang kita alami sekiranya pengenalan terhadapnya tidaklah tertanam dan hadir dalam pikiran kita? Setelah mengelaborasi instrumen empiris seperti di atas, kita bisa dengan mudah menangkap maksud Suhrawardi tentang adanya kesadaran atau pengetahuan dalam diri kita yang tidak diperoleh melalui representasi atau datadata indrawi apapun. Pengetahuan ini hanya terwujud melalui unifikasi eksistensial yang dalam sistem filsafatnya disebut sebagai ilmu hudhuri. Oleh karenanya, ilmu hudhuri harus dipahami sebagai pengetahuan yang di dalamnya realitas objek—dalam hal ini adalah rasa sakit—yang diketahui hadir dalam pikiran subjek—dalam hal ini yang menderita luka di tangan—yang mengetahui tanpa representasi atau data-data indrawi atas subjek tersebut. Setelah memberikan secuplik bukti yang mengukuhkan bahwa Suhrawardi tidak mengabaikan realitas empiris dalam sistem epistemoginya, mari kita melangkah maju dengan menelusuri halaman demi halaman dalam magnum opusnya yang berkaitan erat dengan studi yang kita lakukan. Tepatnya, pada pembagian ilmu pengetahuan menurut Suhrawardi sendiri. Hal ini penting karena akan memberikan pandangan yang utuh bagi kita bahwa, Suhrawardi ternyata tidak hanya menggarap bidang metafisika dalam konsep epistemologinya lalu mengabaikan bidang fisika. Atau, tidak hanya bereksplorasi dalam ranah Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 65 ontologis dan melupakan ranah yang ontis. Atau, tidak hanya menguraikan masalah yang melangit dan mengacuhkan masalah yang membumi. Dalam Hikmah al-Isyraq secara jelas ia menulis: . ﻄ ! وھﻮ ﻣﺤﺎل، وﻻ ﯾﺤﺼﻞ ﻟﮫ أول ﻋﻠﻢ ﻗﻂ،ﻣﺎ ﻻ ﯾﺘﻨﺎھﻰ ﻗﺒﻠﮫ Pengetahuan manusia ada yang fitri dan non-fitri. Suatu objek yang belum diketahui, jika tidak cukup ditangkap dengan isyarat dan getaran instingtif, tidak bisa dicapai dengan pengamatan saksama seperti yang dilakukan para ilmuwan agung, pasti membutuhkan instrumen pengetahuan lain yang secara sistematis bisa membuatnya diketahui, dan berakhir pada kejelasan yang bersifat fitri. Jika tidak, objek itu menjadi tak terjamah nalar manusia, sehingga tidak membuahkan pengetahuan sama sekali. Ini mustahil! (Suhrawardi, 1993, 18). Untuk mengetahui dua jenis ilmu seperti yang diklasifikasikan Suhrawardi dalam kutipan ini tidaklah sulit. Yaitu fitri atau kodrati dan non-fitri atau nonkodrati. Namun untuk mengetahui perbedaan mendasar antara kedua jenis ilmu tersebut tidaklah semudah yang dibayangkan. Hal ini terjadi karena: pertama, dalam lembar-lembar lain dalam karyanya, Suhrawardi tidak pernah memberikan definisi yang jelas atau pengertian yang tegas seputar kedua jenis pengetahuan tersebut. Hal ini wajar karena dalam menguraikan suatu masalah, sejauh penelusuran penulis, Suhrawardi sangat jarang atau bahkan tidak pernah menggunakan metode definisi. Oleh sebab itulah, dibutuhkan kesabaran yang tinggi untuk meneliti halaman demi halaman dalam karya-karyanya supaya kita bisa sampai pada kesimpulan yang valid mengenai hakikat sesuatu yang dibahas, termasuk juga kedua jenis ilmu di atas. Kedua, kebiasaan Suhrawardi dalam menguraikan sesuatu dalam kemasan gaya bahasa bercorak negasi—seperti tergambar dalam uraian mengenai pengetahuan non-fitri di atas, semakin manambah berat upaya kita dalam memahami pemikirannya yang dituangkan dalam premis-premis pendek yang rumit dan terkesan berbelit. Untuk mengatasinya, kita harus mengembangkan pola pikir positif di balik kalimat-kalimat bercorak negasi tersebut, sembari Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 66 menggunakan instrumen ilmu semantik untuk memahami maksud dari paparannya. Dengan menggunakan kedua metode ini, kita bisa memahami makna pengetahuan fitri seperti yang diinginkan Suhrawardi. Baginya, pengetahuan fitri adalah jenis pengetahuan yang bersifat pasti, primer, dan badihi (terbukti dengan sendirinya), serta merupakan dasar bagi seluruh tindak mengetahui itu sendiri. Komentator Suhrawardi yang bernama al-Syirazi mencontohkan pengetahuan tentang diri (ilmu bin nafs), pengetahuan tentang Tuhan (ilm al-bari), serta pengetahuan tentang entitas-entitas jasmani terpisah (ilm al-mujarradat almufaraqah) sebagai jenis pengetahuan yang bisa dikelompokkan ke dalam jenis pengetahuan ini. Jenis pengetahuan ini disebut pasti dan primer karena ia bersifat primordial, mempunyai peran utama dalam bentuk dasar intelek, serta implisit dan inheren bagi seluruh jenis pengetahuan manusia, bahkan merupakan konstituen utama makna pengetahuan itu sendiri. (Ziai, 1998, 135) Dari sinilah penulis akan mengawali langkah pertama memperkenalkan keunikan epistemologi ilmu hudhuri yang dicetuskan oleh Suhrawardi. Dengan mengklasifikasikan pengetahuan intuitif berikut objeknya yang bersifat imanen sebagai ilmu pengetahuan kodrati yang bersifat pasti, pandangan filosofis Suhrawardi sudah berbeda secara diametral dengan Aristoteles yang membangun pengetahuannya dari realitas empiris dan objek-objek transitif. Namun demikian, klasifikasi yang dilakukan Suhrawardi tetap didasarkan pada argumen filosofis yang ketat, dan bukan hanya disandarkan pada egoisme intelektual supaya berbeda dengan pemikir besar Yunani tersebut. Bagi Suhrawardi, ketiadaan objek transitif untuk diacu justru merupakan pijakan kuat untuk menegaskan tingkat kepastian pengetahuan fitri. Mengapa? Karena ketiadaan objek transitif dalam pengetahuan fitri, bukan berarti pengetahuan ini tidak memiliki objek. Pengetahuan firti ini juga memiliki objek sama seperti pengetahuan non-fitri yang akan dibahas kemudian. Namun objeknya berbeda, bersifat imanen dan tidak transitif dalam dunia empiris-eksternal. Objek pengetahuan jenis ini bersifat intellegible dan imaginable, tidak sensible. Para filsuf Muslim biasa menyebut objek semacam ini sebagai ma'qulat. Walaupun Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 67 tidak sama persis, namun objek seperti ini bisa disetarakan dengan dunia idea Plato—sebuah dunia yang menurutnya bersifat abadi, absolut, dan sempurna. Dengan mengasumsikan bahwa objek-objek seperti ini berkarakter unik, sederhana, universal, nonmaterial, dan tak berubah, berarti adalah suatu keniscayaan untuk menobatkan pengetahuan fitri sebagai pengetahuan sejati. Sebab, tingkat kepastian dari objek yang diacu sangatlah baku dan sama sekali tidak mengenal hukum relatifitas atau probabilitas. Objek ini bersifat imanen, intrinsik, wajib, serta merupakan bagian dari aksi subjek yang mengetahui. Pengetahuan fitri ini bisa disamakan dengan matematika yang, untuk memverifikasi kebenaran teorinya, tidak diperlukan objek transitif apapun, tapi cukup dengan menguji konsistensi-logis dari rumus yang merupakan postulat dasarnya. Oleh sebab itulah, dalam al-Masyari' wa al-Mutharahat Suhrawardi menegaskan, untuk menguji tingkat kebenaran dalam pengetahuan ini, tidak diperlukan instrumen yang bernama korespondensi. Sebuah instrumen yang menyaratkan adanya kesesuaian antara objek yang diacu dengan pengetahuan yang didapatkan. Sebab, korespondensi hanya berlaku untuk pengetahuan yang objeknya bersifat eksternal dan transitif. : .ﺣﺼﻞ ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ . : ، ﻓﺈذا ﺣﺼﻠﺖ ﺑﻌﺪ أن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ،اﻟﻤﺬﻛﻮرة . وﻻ ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ،وھﻮ اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻹﺷﺮاﻗﯿﺔ ﻻ ﻏﯿﺮ Tanya: Saat seseorang mengetahui sesuatu, jika tidak mengenal apa-apa, berarti ia tidak mengetahuinya, tapi jika mengenalnya, berarti harus ada korespondensi. Jawab: dalam pengetahuan tentang realitas eksternal memang demikian. Tapi dalam epistemologi iluminasi yang kita bicarakan, jika seseorang telah mengenal sesuatu yang sebelumnya tidak ia kenal, berarti ia telah mengetahuinya. Di sini yang berlaku adalah relasi iluminasi, bukan yang lain. Jadi, tidak perlu adanya korespondensi. (Suhrawardi, 1993, 489) Jenis pengetahuan yang kedua adalah pengetahuan non-fitri. Dari keterangan Suhrawardi di atas, kita bisa dengan jelas mengetahui bahwa jenis pengetahuan ini berkisar pada objek-objek ekstrinsik, aksidental, tidak hadir dalam pikiran, dan berada di luar tindak mengetahui. Oleh karenanya, tingkat kebenaran pada pengetahuan ini benar-benar ditentukan oleh instrumen Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 68 korespondensi. Jika pengetahuan yang diperoleh tidak sesuai dengan realitas yang diacu, praktis, pengetahuan itu tidak benar dan harus dikoreksi. Untuk pengetahuan jenis ini, dalam Hikmah al-Isyraq Suhrawardi secara tandas menyaratkan korespondensi. .ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﻓﺎﻷﺛﺮ اﻟﺬي ﻓﯿﻚ ﻣﺜﺎﻟﮫ Jika idea yang memetakan realitas dalam diri Anda tidak sesuai dengan pengetahuan yang Anda peroleh, berarti Anda harus menyesuaikan pengetahuan itu dengan idea yang Anda miliki. (Suhrawardi, 1993, 15) Setelah berhasil membuktikan bahwa pengetahuan non-fitri dengan segenap objek eksternal empirisnya terjebak pada hukum probabilitas kebenaran karena tak bisa melepaskan instrumen korespondensi, maka dengan sendirinya tak ada yang bisa menghalangi Suhrawardi untuk menganggap pengetahuan jenis ini sebagai pengetahuan biasa yang tidak begitu istimewa. Sebuah pengetahuan yang tingkat akurasi dan kepastiannya tidak konsisten yang tidak sekokoh jenis pengetahuan yang pertama. Dalam dunia modern, jenis pengetahuan non-fitri ini bisa disejajarkan dengan pengetahuan alam atau pengetahuan sosial yang, hukum, rumus, serta semua teorinya bersifat relatif, tidak berlaku universal, serta takkan pernah bisa diangkat kepada keniscayaan logis atau pasti dengan sendirinya. Dengan demikian, kita bisa menjawab pertanyaan, mengapa teori fisika mekanik Newton bisa dipatahkan oleh fisika quantum Enstein? Atau, mengapa setelah melalui rekayasa fisika yang canggih, air tak lagi mendidih pada suhu 100 derajat celcius? Atau dalam ilmu sosial, mengapa teori sosiologi masyarakat Jawa yang dipetakan Clifford Geertz bisa dibuktikan tidak benar? Atau, mengapa teori masyarakat ideal berdasarkan hukum Islam tidak bisa diterapkan di Indonesia, walaupun sukses diaplikasikan di Saudi Arabia? Lebih spesifik lagi, mengapa undang-undang anti pornografi dan pornoaksi mustahil diberlakukan secara universal kepada seluruh penduduk Nusantara? Semua pertanyaan di atas bisa diatasi dengan memberikan satu jawaban refleksif-filosofis; yaitu karena semuanya berada dalam lingkup ilmu pengetahuan non-fitri yang memiliki objek eksternal, transitif, dan empiris. Sebuah pengetahuan yang karena karakter objeknya sendirilah yang membuatnya takkan Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 69 pernah pasti dan niscaya. Penulis yakin, faktor yang sama jugalah—berkaitan dengan data-data indrawi yang empiris—yang menyebabkan teori falsifikasi yang dikemukakan Karl Popper diizinkan untuk mengisi salah satu celah kosong dalam semarak dunia ilmu pengetahuan. Sudah barang tentu semua pertanyaan di atas memiliki jawaban spesifik dengan argumen yang berbeda antara satu sama lain, sesuai dengan wilayah ilmu pengetahuan di mana pertanyaan-pertanyaan itu biasa dikaji. Seperti wilayah fisika, kimia, sosiologi, antropologi, dan lain sebagainya. Namun jawaban spesifik semacam itu hanya berlaku saat kita mengulas ragam persoalan tersebut dalam disiplin ilmunya masing-masing secara partikular, bukan ketika mengulasnya secara universal dalam wilayah ilmu filsafat. 3.4. Landasan Historis Ilmu Hudhuri Dalam bagian kedua karya ini, penulis telah menerangkan sejumlah tokoh dan teori yang, seperti diakui oleh Suhrawardi sendiri, telah memberikan pengaruh besar baginya dalam mengembangkan sistem iluminasi. Dengan demikian, kita mengetahui bahwa filsafat iluminasi bukanlah sebuah mahakarya yang muncul secara tiba-tiba dari kehampaan. Begitu pun Hikmah al-Isyraq, ia bukanlah kitab suci yang lahir dari kekosongan sebagai sebuah bentuk kodifikasi wahyu dari Tuhan. Keduanya—filsafat iluminasi dan Hikmah al-Isyraq—adalah buah kreativitas anak manusia yang dihasilkan dari kejeliannya dalam merajut dan meramu pelbagai konsep yang berserak dan berkembang sebelum masanya sehingga, meskipun telah tampil sebagai sintesa baru yang indah dan memukau, tetap tidak bisa menghilangkan "bahan dasar" yang merupakan komponen penyusunnya. Berdasarkan klaim Suhrawardi bahwa hikmah kebijaksanaan yang ia kemukakan pada dasarnya adalah sama dan berasal dari Hermes, berarti secara historis jejak rekam ilmu hudhuri sudah ada jauh berabad-abad sebelum para filsuf Yunani mensistematisir pemikiran-pemikiran falsafi. Akan tetapi, karena tidak adanya sumber valid yang bisa memandu kita menelusuri pelik-pelik pemikiran Hermes yang juga dikenal sebagai Nabi Idris ini, kelihatannya takkan ada alasan untuk disalahkan jika kita memulai penelitian tentang akar sejarah ilmu Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 70 hudhuri dari tradisi filsafat Greek. Di samping itu, penulis juga yakin bahwa cara ini relatif bisa diterima oleh para pengkaji pemikiran filsafat karena dua alasan. Pertama, adalah fakta yang tak bisa dipungkiri bahwa pemikiran filsafat Yunani dengan segala keterbatasan dan kesederhanaannya tetap dianggap sebagai dasar bagi semua pemikiran filosofis yang berkembang setelahnya. Besarnya pengaruh filsafat negeri dewa-dewi ini bisa tercermin dari ungkapan hiperbolik Alfred North Whitehead dalam pengantar bukunya yang berjudul Process and Reality. Menurutnya, seluruh tradisi filsafat Eropa tak lain merupakan serangkaian catatan kaki atas filsafat Plato. (Whitehead, 1979, xiv) Kedua, kedudukan filsafat Yunani bersifat netral dan bisa diterima oleh semua golongan. Jadi, memulai kajian sejarah pemikiran filsafat dari periode Yunani sangat efektif menghilangkan sentimen-sentimen sekterianisme dan subjektivisme yang masih terpendar dari karya sejumlah pemikir Barat. Bentrand Russel misalnya, meskipun banyak pemikir modern yang sudah menginsafi arti penting filsafat Islam, Russell tetap bersikukuh bahwa filsafat Islam tidaklah penting. Dalam karya besarnya yang berjudul Sejarah Filsafat Barat, ia menulis: Filsafat Arab, sebagai pemikiran orisinal tidaklah penting. Pemikirpemikir seperti Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd pada dasarnya adalah komentator... Peradaban Islam pada masa kejayaannya termashur dalam seni dan keahlian teknis, tetapi tidak menunjukkan kemampuan akan pemikiran spekulatif yang independen dalam masalah-masalah teoritis. (Russell, 2002, 567) Dengan menjadikan filsafat Yunani sebagai latar penelusuran, maka seperti yang dikemukakan oleh Bagus, serpihan-serpihan epistemologi iluminasi sejatinya sudah bisa ditemukan dalam kisah terkenal seputar bayangan Plato dalam gua. (Bagus, 2002, 314) Dalam kisah ini, kita memang bisa menemukan hampir semua komponen yang digunakan Suhrawardi dalam merangkai teori epistemologinya, bahkan seluruh pemikiran filsafatnya. Api yang digunakan sebagai sarana untuk menghasilkan bayangan misalnya, juga termasuk dalam komponen filsafat iluminasi. Demikian juga kegelapan dalam gua, serta keadaan yang terang benderang di luar gua. Semua instrumen ini ada dalam karya-karya Suhrawardi. Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 71 Serpihan lain dari filsafat ini juga bisa ditemukan dalam stoisme yang meyakini bahwa pada manusia terdapat percikan akal universal. Berbeda dari kisah bayangan gua Plato, akal budi universal dalam stoisme tidak digambarkan sebagai terang, melainkan sebagai api. (Bagus, 2002, 314) Kepingan epistemologi hudhuri ini semakin mengkristal di tangan kaum Neoplatonis pagan yang bermula dari Plotinus dan berakhir pada Proclus. Pasalnya, merekalah yang memperkenalkan istilah-istilah emanasi, pemahaman dengan kehadiran, dan pencerahan yang semuanya berfungsi sebagai batu pijakan teori filsafat Suhrawardi mengenai landasan ontologis tertinggi dari semua pengetahuan. Kaum Neoplatonis tanpa bisa diragukan lagi telah memberikan konstribusi besar bagi penyelesaian masalah-masalah penting dalam filsafat, dan secara khusus memberikan tilikan-tilikan baru ke dalam masalah pengetahuan mistik berikut pemahaman mengenai Yang Esa dan Kesatuan. Ketika mengulasan masalah nous—suatu kata yang juga tak ditemukan padanannya dalam bahasa mana pun—misalnya, Plotinus mengatakan bahwa nous adalah suatu Ada yang tak memiliki bagian-bagian, tercipta karena yang Esa, serta bisa mengetahui dirinya sendiri, sehingga yang memandang dan yang dipandang adalah satu. Menurut Russell, jika kita mengikuti analogi Plato tentang Tuhan yang dipersepsikan seperti matahari di mana sumber terang dan yang diterangi adalah sama, maka nous bisa dianggap sebagai cahaya yang dengan itu yang Esa memandang diri-Nya sendiri. (Russell, 2002, 394) Lebih lanjut Plotinus menguraikan bahwa nous inilah yang memungkinkan kita untuk mengenal akal Ilahi yang kita lupakan karena kehendak diri. Untuk mengenal akal Ilahi, kita harus mengenal jiwa sendiri serta mengesampingkan jasmani, indra yang memiliki pelbagai hasrat, dorongan, serta kesia-siaan sehingga yang tertinggal kemudian hanyalah citra intelek Ilahi. Dengan cara inilah kita baru bisa merasakan kesadaran luar biasa yang tak terungkap dengan katakata. Mereka yang dirasuki dan diilhami kekuatan Ilahi setidaknya tahu bahwa mereka memendam sesuatu yang lebih agung di dalam diri mereka, meski mereka tak dapat mengatakan apakah itu. (Plotinus, Enneads, III, 14) Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 72 Menurut Russell, dari ungkapan ini kita bisa menyimpulkan bahwa saat dirasuki dan diilhami oleh kekuatan Ilahi, kita bukan hanya melihat nous, namun juga yang Esa. Dan, ketika sedang berinteraksi dengan-Nya, kita tidak bisa menalar apalagi mengungkapkan visi itu dengan kata-kata. Kita baru mengetahui telah memeroleh visi itu ketika jiwa memperoleh terang yang berasal dari dan merupakan Yang Esa itu sendiri. inilah tujuan sejati yang terpapar di hadapan jiwa. Mendapatkan terang dan menatap yang Esa melalui yang Esa, dan bukan melalui cahaya dan prinsip lain apapun. Menatap yang Esa yang sekaligus adalah sarana untuk mendapatkan visi. Sebab, apa yang menerangi jiwa adalah apa yang juga dilihat olehnya, seperti karena terang matahari itu sendirilah kita melihat matahari. (Russell, 2002, 395) Uraian Plotinus mengenai nous sebagai sarana untuk memperoleh ilham sebagai bentuk pertemuan aktual dengan akal Ilahi ini kemudian mengantarkannya pada uraian mistik yang sangat mendalam tentang ekstase mistik atau ekstase spiritual seperti yang terungkap dalam tulisannya berikut: Sudah sering itu terjadi. Terangkat keluar dari tubuh menuju diriku sendiri; berada di luar segala sesuatu lainnya dan memusat pada diri sendiri, menyaksikan keindahan luar biasa. Kemudian, lebih daripada sebelumnya, merasa yakin berpadu dengan tertb tertinggi. (Plotinus, Enneads, IV, 8) Ekstase mistik seperti yang dialami Plotinus ini sangat populer di kalangan penganut asketisme (baca: kaum sufi) dalam Islam pada abad-abad pertengahan. Salah satu tokoh terbesarnya adalah Manshur al-Hallaj yang tekenal dengan ungkapan luar biasa yang mengantarkannya ke tiang gantungan karena dianggap mengajarkan konsep kesatuan esensial antara manusia dengan Tuhan. Sesuatu yang dianggap tabu dan mustahil dalam Islam mengingat manusia dengan Tuhan adalah dua entitas yang berbeda secara esensial. . ﻓﺈذا أﺑﺼﺮﺗﻨﻲ أﺑﺼﺮﺗﮫ وإذا أﺑﺼﺮﺗﮫ أﺑﺼﺮﺗﻨﻲ.ﻧﺤﻦ روﺣﺎن ﺣﻠﻠﻨﺎ ﺑﺪﻧﺎ Kami adalah dua jiwa yang mendiami satu raga. Jika Anda melihatku maka Anda melihat-Nya. Dan jika Anda melihat-Nya, berarti Anda melihatku. (al-Thawazin al-Azal, 34) Sekadar catatan, menurut Laily Mansur, semua karya al-Hallaj sudah punah karena vonis sesat dijatuhkan terhadapnya, para hakim dan penguasa tidak Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 73 hanya mengeksekusi sang mistikus semata, tapi juga memberangus semua kitabkitabnya. Satu-satunya karya al-Hallaj yang luput dari pemusnahan ini karena berhasil disembunyikan oleh Ibnu Atha', salah seorang pengikutnya adalah alThawazin al-Azal. (Mansur, 2002, 111) Dalam konteks ini kita tidak perlu melibatkan diri dengan persoalan apakah ungkapan al-Hallaj itu bisa dibenarkan atau tidak. Sebab, tujuan utama yang ingun penulis capai adalah memberikan bukti historis seputar alur perkembangan ilmu hudhuri dari tradisi filsafat Yunani hingga tiba dan sempurna di tangan Suhrawardi. Jika kembali kepada uraian Plotinus seputar nous di atas, kita akan menemukan keterangan yang menyatakan adanya kesatuan aktual antara dua modus pengetahuan. Yaitu antara subjek pengetahuan (dalam hal ini adalah yang memandang) serta objek pengetahuan (dalam hal ini adalah yang dipandang). Pada titik ini, kita sudah bisa mengatakan bahwa Plotinus sejatinya sudah membahas semacam ilmu hudhuri yang, boleh jadi belum ia sadari sepenuhnya, sehingga masih belum sempurna dan tidak melibatkan satu modus pengetahuan yang ketiga, yaitu aktivitas mengetahui. Meskipun tingkat urgensi modus yang ketiga ini tidaklah sevital kedua modus pengetahuan yang lain; yaitu subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui, akan tetapi tidak alasan bagi kita untuk mengabaikannya dalam uraianuraian epistemologis. Sebab, dalam paparan mengenai masalah epistemologis, selalu ada tiga modus yang wajib diterangkan secara bernas. [1] Subjek yang mengetahui. [2] Objek yang diketahui. [3] Aktivitas mengetahui. Jika satu saja di antara ketiga modus ini terlupakan, praktis, suatu uraian mengenai epistemologi tidak bisa dianggap valid. Tentang kekurangan ini, Yazdi mengatakan bahwa madzhab fisafat ini (Neoplatonis) tidak secara eksplisit mengidentifikasi modus primordial pengetahuan dengan keadaan-keadaan eksistensial realitas diri itu sendiri, meskipun ketika menjumpai masalah mistisisme ia menyentuh dasar tersebut dan berbicara tentang sejenis ilmu hudhuri, sebagai lawan dari pengetahuan biasa yang berkaitan dengan hubungan subjek-objek. (Yazdi, 2003, 45) Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 74 Lebih jauh lagi, Neoplatonis tidak mencirikan pengertiannya tentang ilmu hudhuri melalui kebenaran eksistensial aktual dari kesadaran mistik tentang yang Esa yang biasa timbul dalam pikiran manusia sebagai salah satu bentuk ilmu hudhuri. Dan, di tangan Suhrawardi, semua langkah itu ada secara nyata dan dijelaskan apa yang dimaksud dengan ilmu hudhuri. Elaborasi arus utama penafsiran Suhrawardi mengenai filsafat Yunani pada akhirnya membawa kepada munculnya sistem iluminasi yang didasaran pada kebenaran logis ilmu hudhuri. Titik kesaaan lain yang terdapat dalam uraian-uaraian Plotinus dengan konsep filsafat Suhrawardi—bahkan dengan pemikiran sufistik secara keseluruhan adalah pengenalan terhadap jiwa sendiri, atau terhadap diri sendiri. Hal ini bisa ditempuh dengan mengesampingkan dimensi jasmani dan ketubuhan dalam diri, untuk kemudian memusatkan perhatian pada dimensi ruhani yang juga merupakan nous. Konsep-konsep penyucian diri semacam ini juga menjadi salah satu tangga dalam dunia sufistik untuk melakukan pendakian spiritual menuju puncak tertinggi, yaitu yang Esa. Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 BAB 4 DIMENSI EMPIRIS EPISTEMOLOGI ILUMINASI 4.1. Teori Definisi Adalah hal yang lumrah jika semua akademisi dari seluruh cabang ilmu pengetahuan mengakui definisi sebagai instrumen penting yang tak boleh diabaikan. Pengakuan ini sudah ada sejak zaman Yunani klasik dan tetap lestari hingga sekarang. Sebagai bukti, Socrates, Plato, dan Aristoteles slih berganti memberikan formula untuk mendapatkan definisi yang akurat. Tokoh yang pertama menggunakan cara dialog melalui tanya jawab yang terus-menerus untuk memperoleh pengertian yang valid tentang sesuatu yang ingin diberi definisi. Tokoh kedua menggunakan cara pemilahan (dikotomi, qishmah), sedangkan tokoh ketiga sudah merasa puas dengan penggunaan per genus et differentian. Para filsuf modern pun tak kalah serius mengulas definisi. Bentham mengemukakan cara paraphrasis untuk menentukan makna, kata, atau kalimat. Charles Stevenson mengajukan konsep definisi persuasif. Sementara Alfred J. Ayer membagi definisi menjadi dua; definisi eksplisit dan definisi yang digunakan. Sedangkan WE Johnson memastikan bahwa untuk mendefinisikan nama, mesti menunjuk entitasnya. (Bagus, 2002, 151-152). Karena pentingnya definisi inilah, tidak salah kiranya jika Aristoteles menyatakan bahwa definisi merupakan pintu ilmu menuju pengetahuan ilmiah. Sebab, definisi tidak hanya berfungsi menyediakan penjelasan lugas bagi istilahistilah kunci dalam suatu kajian, tapi pada titik-titik tertentu, definisi terbukti efektif memberikan pemahaman agar sesuatu bisa dimengerti. Sayangnya, Suhrawardi tidaklah demikian. Dalam penjelasan- penjelasannya yang termuat dalam al-Talwihat, al-Maysari' wa al-Mutharahat, serta Hikmah al-Isyraq, tersirat betapa ia bersikap pesimis terhadap kemampuan defiisi untuk mengungkap kebenaran, lebih-lebih memberikan pengetahuan baru. Untuk membuktikan keraguannya ini, Suhrawardi kemudian menetapkan 3 syarat yang sangat ketat terhadap pembentukan definisi. Syarat pertama terangkum dalam kalimat berikut: Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 76 ﺄﻣﻮر .ﺗﺨﺼﮫ إﻣﺎ ﻟﺘﺨﺼﯿﺺ اﻷﺣﺎد أو ﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﺒﻌﺾ أو ﻟﻺﺟﺘﻤﺎع Untuk mendefinisikan sesuatu bagi yang tidak tahu, maka definisi harus mengklasifikasi segala hal yang membuat objek itu spesifik, baik dalam satuan, parsialitas, atau kolektivitasnya. (Suhrawardi, 1993, 18). Berdasarkan syarat ini, berarti definisi bisa dikatakan valid jika ia mampu secara benar menyebutkan satu demi satu semua atribut esesnsial yang, secara kolektif, ada pada benda yang didefinisikan itu, walaupun atribut-atribut tersebut bisa saja secara tersendiri ada pada benda lain. Iqbal menyimpulkan bahwa pada tataran ini, pandangan Suhrawardi sangat mirip dengan Bosanquet. (Iqbal, 1995, 98). Masalahnya adalah, mampukah definsi mengurai semua atribut esensial yang melekat pada objek yang akan didefinisikan? Kalau pun dipaksakan, maka definisi yang dihasilkan pasti berbentuk uraian panjang yang melelahkan dan tidak efektif, bahkan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan deretan kerumitan-kerumitan baru sebagai akibat dari rincian yang begitu subtil. Sebagai misal, mendefinisikan manusia sebagai "animal rationale" tidak bisa dikatakan valid karena "berpikir" bukan satu-satunya atribut yang dimiliki oleh manusia. Masih banyak atribut lain yang tidak terakomodasi dalam definisi tersebut, seperti bekerja, berkeyakinan, beribadah, berbudaya, bermasyarakat, dan lain sebagainya. Kita tidak mungkin menyela dengan menyatakan bahwa bekerja, berbudaya, bermasyarakat, dan ragam atribut lain itu adalah cerminan dari berpikir, sehingga mendefinisikan manusia sebagai "hewan yang berpikir" sudah bisa dikatakan valid. Sebab, tuntutan Suhrawardi dalam syarat yang pertama ini adalah keluasan definisi dalam memuat semua atribut kolektif, parsial, serta satuan yang dimiliki oleh objek yang didefinisikan, bukan dengan memberikan predikat tertentu yang membuat objek itu bisa dibedakan dengan objek yang lain. Syarat kedua adalah: .أو ﯾﻜﻮن ﻻ ﯾﻌﺮف إﻻ ﺑﻤﺎ ﻋﺮف ﺑﮫ Definisi harus dibangun dengan sesuatu yang lebih jelas bukan dengan sesuatu yang memiliki kejelasan serupa, terlebih dengan sesuatu yang tidak jelas, atau tidak diketahui kecuali melalui yang akan diberi definisi. (Suhrawardi, 1993, 18). Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 77 Kendati tidak dinyatakan secara tegas, namun kita bisa menangkap bahwa makusd di balik penetapan syarat ini adalah, supaya definisi menghasilkan pengetahuan baru, tidak bersifat tautologis, atau hanya berbentuk penggantian nominal belaka. Dengan demikian, mendefinisikan "ayah" sebagai orang yang mempunyai anak, tidak bisa dikatakan valid, karena tidak mendatangkan pengetahuan baru. Definisi semacam ini menurut Suhrawardi tidak bisa dibenarkan karena definiendum memiliki kedudukan yang setara dengan definiens-nya. Dengan kata lain, saat mengetahui salah satunya, secara otomatis, kita akan mengetahui yang lainnya. (Suhrawardi, 1993, 18). Dalam Metafisika Persia, Iqbal melengkapi uraian Suhrawardi ini dengan menyajikan contoh bagi definisi yang dibangun dengan sesuatu yang tidak jelas, atau tidak diketahui kecuali melalui yang akan diberi definisi. Contohnya adalah mendefinisikan kuda sebagai "hewan yang meringkik." Menurutnya, kita mengerti hewan, karena kita mengetahui banyak hewan yang di dalamnya atribut ini ada. Tetapi tidak mungkin mengetahui atribut "meringkik" karena atribut ini hanya dijumpai pada objek yang didefinisikan tersebut. Jadi, definisi semacam ini tidak bermakna karena tidak menghasilkan pengetahuan baru bagi orang yang belum pernah melihat kuda. (Iqbal, 1995, 98). Sedangkan syarat yang terakhir adalah: .ﻣﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﮫ اﻟﺸﻲء أن ﯾﻜﻮن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﻲء ﻻ ﻣﻊ اﻟﺸﻲء Sesuatu yang akan digunakan untuk mendefinisikan, harus sudah diketahui sebelum objek yang didefinisikan, jadi, keduanya tidak bersamaan. (Suhrawardi, 1993, 18). Dalam konteks ini, Suhrawardi tidak ingin jika definisi hanya memuat rangkaian kalimat identis, di mana objek yang didefinisikan terpotret memiliki kesamaan identik dengan rangkaian kalimat yang mendefinisikannya. Menurutnya, definisi atas suatu esensi tidak boleh hanya berupa penggantian kata. Sebab, definisi semacam itu hanya bisa dipahami oleh orang yang sudah mengetahuinya, tapi tidak bagi orang yang belum mengetahui. Contohnya adalah mendefinisikan api sebagai "elemen kimiawi serupa nyawa", atau mendefinisikan matahari sebagai "bintang yang terbit pada siang hari." Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 78 Kedua contoh definisi ini tidak valid karena api dan elemen kimiawi bukan hanya identis, tapi juga memiliki tingkat kebersamaan untuk diketahui. Demikian juga dengan definisi matahari sebagai bintang yang terbit siang hari. Kenyataan faktual membuktikan bahwa siang sangat identik dengan matahari, dan matahari sangat identik dengan siang. Jadi, kedua unsur definisi ini datang secara bersamaan ke dalam pemahaman. Pesimisme Suhrawardi terhadap kemampuan definisi dalam memberikan pengetahuan baru yang akurat semakin kentara, saat ia menguraikan adanya 3 hambatan yang pasti dijumpai saat seseorang berusaha mendefinisikan sesuatu. Hambatan ini bisa berasal dari subjek yang hendak mendefinisikan, atau dari objek yang hendak didefinisikan, atau bahkan karena kompleksitas definisi itu sendiri. Hambatan pertama adalah keterbatasan manusia dalam mempersepsi sesuatu. Secara natural, memang tidak bisa dipungkiri bahwa manusia adalah makhluk terbatas yang mustahil mampu mempersepsi sesuatu secara utuh, menyeluruh, murni, dan apa adanya. Instrumen apa pun yang digunakan manusia dalam upaya mengetahui sesuatu, pasti terbentur pada dinding keterbatasan yang membuatnya kesulitan untuk mencapai pengetahuan yang esensial dan komprehensif. Untuk mengatasi keterbatasan indra dalam mendapatkan gambaran yang utuh tentang suatu objek, Edmund Husserl kemudian menawarkan konsep konstitusi. Sedangkan untuk mengatasi keterbatasan subjektivisme yang rentan membuat objek tak lagi murni, ia menawarkan teori reduksi. Jauh sebelum Husserl menyadari keterbatasan ini, Suhrawardi sudah menyatakan bahwa objek apapun yang berusaha ditangkap manusia sangatlah rumit dan kompleks, sehingga hampir tidak mungkin diketahui seluruhnya. Pada pragraf terakhir pasal ke-15 aksioma ke-7 dalam Hikmah al-Isyraq, ia menulis: ... " إذ " ... ،ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت ﻏﯿﺮ ﻇﺎھﺮة .ﯾﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻣﺘﯿﻘﻨﺔ Orang yang menyatakan telah mengetahui esensi sesuatu, tidak menutup kemungkinan ada esensi lain yang belum ia ketahui..., oleh sebab itulah, pendefinisi tidak boleh berkata, "Seandainya ada sifat lain (dari objek Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 79 yang didefinisikan) aku pasti mengetahuinya." Karena banyak sifat-sifat (dari objek yang didefinsiikan itu) tidak tampak..., bila ada satu esensi saja yang luput dari pengamatan, maka pengetahuam atas realitas menjadi tidak meyakinkan. (Suhrawardi, 1993, 21) Hambatan yang kedua adalah kompleksitas proses definisi itu sendiri. Dalam al-Talwihat bab kedua, Suhrawardi menyatakan bahwa, untuk mendefinisikan sesuatu, tidak cukup hanya dengan menyebutkan esensi alaminya saja. Pasalnya, selain ciri khusus yang dimiliki sesuatu itu, ia juga memiliki sifatsifat lain yang menyertainya, yang juga harus dipertimbangkan dalam proses pembuatan definisi. Oleh karena itu, sebuah definisi tidak cukup hanya dengan menyebutkan esensi paling khusus dari sesuatu, tetapi juga harus menyertakan sifat-sifat lainnya. Saat mendefinisikan manusia sebagai hewan rasional, kita memang telah menyebutkan esensi paling khusus dari manusia, yaitu berpikir. Akan tetapi, kita belum menyebutkan esensi atau sifat-sifat lain yang juga merupakan esensi manusia, walaupun bukan yang paling khusus. Kesulitan yang menghambat kita pada tataran ini adalah keterbatasan untuk menguraikan pelbagai sifat bawaan yang melekat kepada manusia. Dari keharusan menyebutkan sifat-sifat lain yang berdampingan dengan sifat khusus yang dimiliki sesuatu yang didefinisikan, maka kita dapat menyimpulkan bahwa pengetahuan melalui definisi tidaklah sempurna. Mengapa? karena kita takkan pernah mengetahui semua sifat-sifat bawaan yang terdapat pada segala sesuatu. (Razavi, 1997, 94) Hambatan ketiga sekaligus yang terakhir, berasal dari objek yang akan didefinisikan. Di antara sekian banyak realitas dalam kehidupan, ada sesuatu yang hanya memiliki genus, tapi tidak memiliki deferensia sehingga tidak dapat didefinisikan. Misalnya adalah warna, suara, atau bau. Suhrawardi mencontohkan warna "hitam" sebagai sesuatu yang hanya bisa didefinisikan oleh dirinya sendiri. dalam Hikmah al-Isyraq ia menulis: اﻟﺴﻮاد ﺷﻲء واﺣﺪ ﺑﺴﯿﻂ وﻗﺪ ﻋﻘﻞ . وﻣﻦ ﺷﺎھﺪه اﺳﺘﻐﻨﻰ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ،ﺗﻌﺮﯾﻔﮫ ﻟﻤﻦ ﻻ ﯾﺸﺎھﺪه ﻛﻤﺎ ھﻮ Warna hitam adalah suatu objek yang sederhana, terasionalisasi, dan tidak terbagi dalam partikel-partikel yang tidak diketahui. Orang yang tidak Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 80 menyaksikannya tidak dapat mendefinisikannya, dan orang yang menyaksikannya tidak butuh definisi. (Suhrawardi, 1993, 73) Di samping, warna, suara, dan bau, masih banyak lagi realitas lain yang hanya memiliki genus tapi tidak memiliki deferensia, sehingga satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah dengan berinteraksi langsung dengannya. Rasa manis misalnya, ia juga merupakan objek sederhana yang hanya mungkin diketahui oleh orang yang mengecapnya. Jadi, seberapa pun panjangnya uraian definitif tentang manis, sama sekali takkan pernah mendatangkan pengetahuan apa-apa bagi orang yang tidak merasakannya secara langsung. Suhrawardi sejatinya ingin menegaskan bahwa pengetahuan tentang sesuatu ditentukan oleh hubungan antara subjek dengan objek, tanpa halangan apa pun. Hubungan langsung antara subjek dan objek inilah yang ia sebut sebagai hubungan iluminasi (idhafah isyraqiyyah). Menurutnya, jika sesuatu sudah terlihat, maka seseorang sudah tidak lagi membutuhkan definisi. Sebab, bentuk sesuatu yang terkonstruksi dalam pikiran, adalah sama dengan bentuk sesuatu yang ada dalam persepsi indra. Baginya, pengetahuan yang diperoleh melalui persepsi ini disebut musyahadah (penyaksian). Pengetahuan semacam ini jauh lebih tinggi dari pengetahuan predikatif. Akan tetapi, betapa pun besarnya pesimisme Suhrawardi terhadap peranan definisi dalam memberikan pengertian dan pemahaman, ia tetap sadar bahwa definisi merupakan ornamen strategis dalam ranah ilmu pengetahuan yang tak mungkin dicampakkan begitu saja. Ia menginsafi bahwa, meskipun ada cara lain yang bisa digunakan untuk menyingkap pengetahuan, definisi tetaplah sarana yang, pada titik-titik tertentu masih diperlukan. Oleh sebab itulah, ia kemudian merumuskan sendiri teori definisi yang menurutnya bisa memberikan pengetahuan valid yang tak bisa diragukan. Rumusan itu ia tuangkan dalam kalimat pendek—namun syarat makna dan multi interpretasi—seperti berikut ini. . .ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت ﺑﺄﻣﻮ ﺗﺨﺺ ﺑﺎﻻﺟﺘﻤﺎع Sesuatu itu (baru bisa dikatakan) diketahui jika semua esensinya diketahui. Jadi bagi kita, definisi hanya diperoleh dengan perantaraan sesuatu yang secara khusus berkaitan dengan keseluruhan sesuatu. (Suhrawardi, 1993, 21) Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 81 Kalimat jami'u dzatiyyatiha (semua esensinya) dalam rumusan di atas harus kita beri perlakuan khusus dan kita renungkan secara mendalam. Mengapa? Karena kita berbicara dalam konteks filsafat iluminasi yang, salah satu keunikannya adalah mengombinasikan unsur yang empiris dan intuitif. Apalagi bagi Suhrawardi, esesnsi sesuatu itu tidak terlepas darinya baik secara nyata ataupun secara mental. Karena itu, sesuatu tidak dapat mempunyai definisi esensial semata, karena itu berarti bahwa sesuatu memiliki sifat-sifat pokoknya yang "terpisah" ke dalam genus dan diferensia. Akan tetapi, hanya dapat digambarkan sebagaimana ia terindra. Oleh sebab itu, untuk mendefinisikan sesuatu, seseorang harus "melihat"nya sebagaimana adanya. Bagian kedua dari rumusan Suhrawardi yang tersimpul dalam kalimat "definisi hanya diperoleh dengan perantaraan sesuatu yang secara khusus berkaitan dengan keseluruhan sesuatu" kental dengan aroma Aristotelian, karena memberi peluang pada objek yang didefinisikan untuk diuraikan secara naratif. Sedangkan penekanan pada keharusan untuk mengetahui semua esensi seperti yang tersimpul dalam kalimat, "Sesuatu itu (baru bisa dikatakan) diketahui jika semua esensinya diketahui" syarat dengan nuansa Platonian, di mana untuk mengetahui suatu objek secara benar, seseorang tidak cukup hanya mengetahui benda empiriknya saja, tapi juga harus mengetahui idea yang menjadi konsep mental objek tersebut. Atas dasar itulah, banyak peneliti yang kemudian menyimpulkan bahwa teori definisi yang digagas Suhrawardi sejatinya adalah elaborasi dari teori definsi yang digagas oleh Plato dan Aristoteles. Hossein Ziai, menyebut teori definisi ini sebagai definisi konseptualis khas Suhrawardi. (Ziai, 1998, 82) Sayangnya, kita takkan pernah menemukan uraian yang tuntas mengenai konsep definisi ini dalam semua karya yang ditulis Suhrawardi. Jadi, Suhrawardi tidak menerangkan langkah operasional, proses pembentukan, apalagi contoh kongkrit dari definisi tersebut. Padahal, saat mengulas tentang syarat dan berbagai keterbatasan definsi, ia bisa memberikan keterangan yang rinci lengkap dengan contoh-contoh yang memuaskan. Keputusan Suhrawardi untuk tidak menguraikan teori definisi yang digagasnya itu secara spesifik sebenarnya bisa dimaklumi, mengingat sejak awal Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 82 dia sudah bersikap apriori terhadap definsi—khususnya definsi Aristotelian— dalam mencapai pengetahuan. Atau, boleh jadi ia sengaja menggantung teori definisi yang ia kemukakan karena pembuatan definisi semacam itu memang mustahil untuk diwujudkan. Setelah mengklaim definisi seperti yang lazim kita kenal sebagai metode yang kurang memuaskan, atau bahkan tidak valid untuk memperoleh pengetahuan, pertanyaannya sekarang, meode apa yang ditawarkan Suhrawardi untuk mengetahui sesuatu yang bisa menggantikan kedudukan metode definisi? Dalam bahasa yang berbeda, bagaimana menurutnya cara mengetahui sesuatu? Di sinilah kemudian letak keunikan gagasan Suhrawardi. Ia mengajukan suatu formula unik yang sekaligus menjadi ciri khas epistemologi iluminasi dalam proses mengetahui. Ia menawarkan teori penyaksian yang dalam terminologi Arab biasa disebut dengan musyahadah, sedangkan dalam terminologi Inggris biasa disebut vision. 4.2. Teori Penyaksian Bagi Suhrawardi, cara terbaik dan tervalid untuk mengetahui sesuatu adalah menggabungkan dua pendekatan secara integral, yaitu pendekatan mental dan visi langsung terhadap objek yang diketahui. Sebab, hanya dengan cara ini suatu objek benar-benar bisa dirasakan, dan seseorang tak lagi membutuhkan definisi. Dua pendekatan ini akan menghasilkan pengetahuan komprehensif yang nilainya lebih bisa dipertanggungjawabkan dibandingkan dengan pengetahuan yang diperoleh secara predikatif. Ketika seseorang (baca: subjek) menangkap sesuatu (baca: objek) secara visioner dan intuitif, maka ia akan sampai pada pengetahuan sejati terhadap objek itu tanpa perantaraan predikat. Tentang hal, ini Hossen Ziai menyatakan bahwa konsep penyaksian (Musyahadah) yang dikemukakan Suhrawardi, sejatinya bertujuan menghasilkan pengetahuan murni yang bisa dituangkan dalam proposisi esensial "X adalah," bukan prosisi predikatif yang biasa dilambangkan dengan "X adalah Y". (Ziai, 1998, 131) Dalam Hikmah al-Isyraq, Suhrawardi menegaskan bahwa proses visi bukan terjadi karena terciptanya ilustrasi objek yang terlihat di pelupuk mata, atau Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 83 kerena mata memancarkan cahaya kepada objek yang terlihat. Akan tetapi, karena mata yang sehat menangkap cahaya yang dipancarkan oleh objek tertentu. Hasil dari penangkapan ini adalah, hilangnya pelbagai tirai—baik yang bersifat mental atau pun material—antara subjek dan objek. . ﺑ .اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﯾﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﻋﺪم اﻟﺤﺠﺎب ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺎﺻﺮ واﻟﻤﺒﺼﺮ Pandangan bukan karena terciptanya ilustrasi objek pada mata, juga bukan karena keluarnya sesuatu dari mata, akan tetapi karena penerimaan mata yang sehat teradap objek yang bercahaya, tidak lebih. Penerimaan ini menghasilkan tidak adanya penghalang antara yang melihat dengan yang terlihat. (Suhrawardi, 1993, 134) Sekilas, pandangan Suhrawardi ini sama dengan hukum fisika modern yang menyatakan bahwa, kita bisa melihat benda karena benda itu memancarkan cahaya kepada mata, bukan mata kita yang memancarkan cahaya kepada benda itu. Dalam teori ini, subjek yang melihat seolah terkesan pasif, sementara objek yang terlihat terkesan aktif. Mata sebagai instrumen yang dimiliki subjek untuk mengetahui berada pada posisi menerima data, sedangkan benda yang terindra berfungsi sebagai pemberi data. Pada titik inilah, kita melihat perbedaan yang signifikan antara teori penyaksian Suhrawardi dengan hukum fisika modern. Baginya, dalam proses penyaksian ini, kedua pihak, subjek dan objek harus sama-sama aktif dan tidak ada yang bersifat pasif. Makanya, ia menyaratkan keharusan adanya dua cahaya yang bertemu dalam proses penyaksian, cahaya dari subjek dan cahaya dari objek. Kedua cahaya ini harus bertemu sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan penangkapan esensial yang bermuara pada pengetahuan sejati tentang objek yang terlihat tersebut. Apabila salah satu pihak bersikap pasif, semisal subjek memejamkan mata lalu berinisiatif mengetahui suatu objek dengan menghayal, hal ini takkan menghasilkan pengetahuan karena proses penyaksian tidak berlangsung sempurna. Mata yang terpejam bukan hanya tidak bisa menerima cahaya yang dipancarkan objek, tapi juga tidak bisa memancarkan cahaya untuk memindai objek tersebut. Jadi, pada tataran ini, epistemologi hudhuri benar-benar hanya Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 84 menentukan cara memperoleh ilmu pengetahuan ketika kita sedang sadar dan melakukan proses pengindraan terhadap sesuatu, bukan saat kita sedang berimajinasi atau merenungkan sesuatu. Untuk menghasilkan penyaksian yang benar, Suhrawardi menetapkan dua syarat yang harus dipenuhi oleh subjek. Pertama, pandangan tidak boleh terlalu dekat kepada objek, karena takkan menghasilkan persepsi yang utuh tentang objek. Kedua, pandangan juga tidak boleh terlalu jauh dari objek, karena rentan terhadap berbagai halangan. Dengan kata lain, Suhrawardi sebenarnya ingin menganjurkan agar subjek menentukan jarak yang ideal dengan objek. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Konsep penyaksian yang dikemukakan Suhrawardi ini akan mudah dipahami jika kita menggunakan contoh praktis yang lazim ditemui dalam realitas keseharian. Untuk mengetahui gajah misalnya, kita harus menentukan posisi yang tepat agar bisa melihat hewan itu dengan jelas dan akurat. Saat terlalu dekat, praktis, gambaran yang kita peroleh takkan sempurna, karena boleh jadi ada bagian-bagian tertentu dari binatang besar itu yang tidak terlihat. Tapi juga tidak boleh terlalu jauh. Mengapa? Karena meskipun kita mendapatkan gambaran yang utuh tentang gajah, kita pasti melewatkan detil-detil tertentu dari hewan itu yang, boleh jadi merupakan keunikan dan ciri khas yang membedakannya dari binatang lain, seperti tekstur kulit atau anatomi lututnya yang hanya bisa dilihat dari dekat. Sejauh ini, penulis telah memaparkan pendekatan unik dalam mengetahui objek yang berlaku dalam wilayah filsafat iluminasi. Sebuah pendekatan yang mengutamakan unsur pengindraan langsung antara subjek dengan objek sehingga diperoleh pengetahuan yang esensial dan valid. Namun demikian, masih tersisa sekelumit pertanyaan, sehebat apakah metode penyaksian (musyahadah) ini sehingga bisa dikatakan sebagai sarana yang bisa mengantarkan kita pada pengetahuan yang bersifat esensial? Misalnya, bisakah kita telah mengetahui esensi manusia dengan hanya melihat seorang pria atau wanita? Seakan sudah mengetahui bahwa pertanyaan seperti ini akan terlontar, Suhrawardi mengantisipasinya dengan mengajukan teknik khusus agar proses penyaksian (musyahadah) kita sampai pada pengetahuan yang bersifat esensial terhadap sesuatu. Menurutnya, untuk mengetahui suatu objek secara esensial, Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 85 langkah mutlak yang harus dilakukan adalah mengamati suatu objek secara an sich, apa adanya, dan mengabaikan segala pengaruh eksternal di luar objek tersebut. Pengamatan yang fokus seperti ini dengan sendirinya akan membuat kita bisa membedakan antara unsur esensial dan yang aksidental yang dimiliki oleh suatu objek. Jika unsur yang paling esensial ini sudah berhasil ditangkap, berarti pengetahuan kita tentang objek itu sudah benar-benar valid dan akurat. Tapi persoalannya adalah, bagaimana cara kita membedakan antara unsur yang esensial dan aksidental pada suatu objek? Bukankah seandainya kita salah menentukan, menganggap suatu unsur sebagai esensial padahal sebenarnya aksidental, pengetahuan yang kita peroleh pun tidak benar? Supaya kita tidak keliru dalam membedakan antara unsur yang esensial dan aksidental, maka satu-satunya cara menurut Suhrawardi adalah menemukan satu esensi yang mustahil terlepas dari objek tersebut. Suatu esensi yang mengikuti laju eksistensi, muncul dan mengada karena objek tersebut. Cirinya adalah, rasionalisasi esensi itu mendahului rasionalisasi atas keseluruhan objek, dan bisa memberikan gambaran yang utuh dan menyeluruh terhadap objek tersebut. .ﻓﺎﻧﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ وﺣﺪھﺎ واﻗﻄﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻏﯿﺮھﺎ ... ﻓﻤﻮﺟﺒﮫ وﻋﻠﺘﮫ ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ،اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ وھﻮ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺤﻘﯿﻘﺔ . وأن ﻟﮫ ﻣﺪﺧﻼ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻜﻞ،ﺗﻌﻘﻠﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻘﻞ اﻟﻜﻞ Amati objek itu secara fokus, dan singkirkan pengamatan kepada yang lain. Esensi yang tak mungkin dipisahkan dan menyertai objek, maka keberadaannya adalah sama dengan keberadaan objek itu... Cirinya adalah bahwa rasionalisasinya mendahului rasionalisasi atas keseluruhan objek, dan punya peluang merealisasikan seluruh objek. (Suhrawardi, 1993, 16) Suhrawardi kemudian memberikan contoh segitiga. Menurutnya, esensi paling mendasar yang tak mungkin dilepaskan dari objek yang bernama segitiga ini adalah, "tiga sudut." Dengan menemukan esensi ini, berarti subjek atau seseorang sudah mengetahui elemen yang paling substantif dari objek segitiga. Pasalnya, esensi ini bisa memberikan gambaran yang utuh tentang segitiga secara general. Dengan kata lain, ketika seseorang sudah mengetahui "tiga sudut" sebagai esensi segitiga, maka ia sudah bisa mempersepsi segala jenis dan ukuran Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 86 segitiga dalam dunia realitas. Berapa pun ukuran bangun segitiga yang dijumpai, atau terbuat dari materi apapun sebuah bentuk segitiga, sudah tidak menjadi masalah lagi. Seseorang sudah bisa mengonsepsinya secara utuh. Dan, saat esensi ini sudah diketahui, berarti orang itu sudah tidak membutuhkan definisi lagi tentang segitiga. Alasan lain di balik penetapan "tiga sudut" ini sebagai esensi yang paling substantif dari segitiga adalah karena, esensi ini pasti muncul dan mengada bersamaan dengan segitiga. Esensi ini selalu mengikuti laju setiap segitiga, kapan pun, di mana pun, dan dalam konteks apapun. Artinya, seseorang tidak mungkin merekayasa bentuk segitiga sedemikian rupa, sehingga misalnya, ia bisa membuat segitiga dengan sudut kurang atau lebih dari tiga. Jadi, kalau ada orang yang memaksa akan membuat segitiga dengan 4 sudut, maka yang ia hasilkan pasti segi empat, bukan lagi segitiga. Sebaliknya, jika ia berusaha membuat segitiga dengan dua 2 sudut, maka yang ia hasilkan juga bukan segi tiga. Pengetahuan tentang esensi ini demikian penting dalam wilayah epistemologi iluminasi, sehingga Suhrawardi memberikan penjelasan yang agak detil dan akurat. Dalam paparan-paparan selanjutnya, ia mengatakan bahwa tidak setiap objek hanya memiliki satu esensi. Ada sejumlah objek yang memiliki sejumlah esensi, dan kesemuanya itu juga harus diketahui, jika seseorang ingin mendapatkan pengetahuan yang benar tentang sesuatu. Hal ini sejatinya dilandasi usaha Suhrawardi untuk bersikap konsisten dalam merumuskan teori pengetahuan, di samping memang, dalam dunia realitas yang serba kompleks ini, kita banyak menemui suatu objek yang bersifat majemuk, dan tidak sesederhana seperti segitiga yang dicontohkan di atas. Di sisi lain, jika ia menggeneralisir semua objek hanya memiliki satu esensi substantif, maka secara otomatis membuka peluang terhadap kemungkinan semua objek yang ada di dunia ini bisa didefinisikan dalam formula genus per differentia, seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles. Atas dasar itulah, Surawardi bersikap realistik dengan menerangkan pembagian objek berdasarkan karakternya masing-masing berikut bagaimana cara penyaksian bisa dioperasikan terhadapnya. Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 87 4.3 Teori Objek Dalam Hikmah al-Isyraq, secara terpisah Suhrawardi membagi objek atau semua realitas di dunia ini menjadi dua. Pertama adalah realitas sederhana, monolit, simpel, dan tidak memiliki gambaran sepotong-potong dalam akal. Untuk objek ini, Suhrawardi mencontohkan "warna", lebih spesifiknya lagi warna "putih" pada salju, pada gading gajah, atau pun benda yang lain. (Suhrawardi, 1993, 17). Sebelum lebih jauh, penulis ingin mengingatkan supaya kita memfokuskan pada objek yang bernama warna "putih", bukan pada benda-benda tertentu yang secara natural memiliki warna putih seperti dua contoh yang dikemukakan tersebut. Terlepas apakah warna tersebut selalu identik dengan suatu benda, dan mustahil berdiri sendiri secara mandiri, adalah persoalan lain yang, nyaris atau bahkan tidak ada relevansinya dengan kajian kita. Bagi Suhrawardi, "putih" adalah entitas general yang mewujud dalam pikiran, sekaligus objek monolit yang mustahil dipilah dan dipisah ke dalam bagian-bagian yang lebih sederhana. Sebagai objek yang sederhana, "putih" sudah barang tentu tidak mungkin bisa dilukiskan atau digambarkan oleh orang yang tidak melihatnya sebagaimana ia adanya. Akan tetapi, bagi orang yang melihatnya, praktis, ia tak lagi membutuhkan definisi untuk mengetahui lebih baik tentang objek ini. Mengapa? Karena ia sudah sampai pada keadaan yang oleh Suhrawardi disebut, musyahadah; memahamii sesuatu secara utuh. Suatu keadaan yang ditandai dengan terhubungnya pandangan sebagai suatu pertemuan aktual antara subjek yang melihat dengan objek yang terlihat tanpa halangan apapun. Kedua, adalah objek majemuk, rumit, kompleks, dan terdiri dari sejumlah bagian yang berfungsi sebagai penopang sekaligus penyusunnya. (Suhrawardi, 1993, 15). Untuk objek ini, Suhrawardi mencontohkan hewan. Menurutnya, hewan tersusun dari dua esensi. [1] Organ-organ tubuh yang juga disebut sebagai esensi general, [2] Nyawa yang juga disebut sebagai esensi spesifik. Suhrawardi mulai membangun argumennya dengan menyatakan bahwa organ-organ tubuh disebut sebagai esensi general (al-juz al-'am) karena konsepsi mengenai organ-organ tubuh itu bersifat lebih umum dibandingkan dengan Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 88 konsepsi hewan itu sendiri. Sedangkan nyawa ia tempatkan sebagai esensi spesifik dengan alasan, ia adalah bagian mental yang terjadi secara per se. Dengan kata lain, Suhrawardi sejatinya ingin menegaskan bahwa organorgan tubuh merupakan esensi yang lebih utama bagi hewan, karena jika organorgan ini tidak menyatu, maka ada kemungkinan kita tak lagi mampu untuk mengenalinya lagi sebagai hewan, atau benda lain. Akan tetapi, meskipun nyawanya sudah tidak ada, dalam artian hewan tersebut sudah mati, kita masih bisa dengan mudah mengenalinya sebagai hewan. Pemetaan Suhrawardi dengan menempatkan dimensi materi pada hewan sebagai unsur yang general, sedangkan dimensi ruhani sebagai unsur yang spesifik, jangan disimpulkan bahwa ia adalah pemikir bertipe empirismematerialisme yang lebih mengutamakan dimensi materi dibanding dengan dimensi ruhani. Sama sekali tidaklah demikian. Malah sebaliknya, dari karya-karya yang dia tulis, tersirat secara jelas betapa dia sangat mengagungkan dimensi ruhani, khususnya bagi manusia, dibanding dengan dimensi materinya. Jadi, pemetaan semacam ini hanya dilakukan untuk mempermudah proses pemahaman kita dalam mengkaji gagasan epistemologinya. Lebih lanjut Suhrawardi menerangkan bahwa esensi spesifik tersebut adakalanya beriringan dengan esensi spesifik yang lain, seperti "berpikir" pada manusia. Dan adakalanya juga esensi ini lebih khusus dari objek yang bersangkutan. Contohnya adalah gender "kelelakian" bagi manusia. Banyaknya esensi yang dimiliki oleh realitas atau objek majemuk inilah yang, menurut Suhrawardi, membuatnya mustahil bisa dikatakan telah diketahui secara benar jika hanya dilukiskan dengan untaian kalimat-kalimat definisi. Oleh sebab itulah, satu-satunya cara untuk mengetahui realitas ini adalah dengan berusaha mengetahuinya melalui dirinya sendiri melalui sebuah formula yang disebut dengan penyaksian (musyahadah). Dari paparan di atas bisa disimpulkan bahwa dalam teori penyaksian, langkah untuk memahami objek yang tunggal dan sederhana, ditempuh dengan mengetahui esensinya. Sedangkan untuk objek yang kompleks dan majemuk, langkah yang ditempuh adalah dengan mengetahui sifat-sifat dari esensinya. Ini berarti, untuk memperoleh suatu pengetahuan, suatu bentuk kesatuan harus Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 89 dibangun antara subjek dengan objek, di mana keadaan psikologis subjek merupakan faktor yang menentukan dalam membangun pengetahuan ini. Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 BAB 5 DIMENSI INTUITIF EPISTEMOLOGI ILUMINASI 5.1 Teori Cahaya Penulis sengaja mengawali kajian pada bagian ini dengan memaparkan sekilas tentang konsep cahaya dalam filsafat iluminasi. Paparan ini sangat penting mengingat Suhrawardi membangun sistem filsafatnya dengan menggunakan terminologi tunggal yang unik, yaitu cahaya. Dan ini jugalah yang membuatnya digelari sebagai Syaikh al-Isyraq yang berarti Guru Besar Iluminasi, sedangkan teori filsafatnya disebut Hikmah al-Isyraq, Filsafat Iluminasi. Pada sejumlah kesempatan dalam sejumlah bukunya, Suhrawardi berkalikali menekankan pentingnya menginsafi konsep cahaya guna memahami bangunan filsafatnya secara keseluruhan. Ia menegaskan bahwa kaum iluminasionis hanya mengulas masalah cahaya, tidak lebih dari itu. Dan, semua prinsip dalam sistem filsafat ini dibangun berdasarkan penalaran yang menggunakan instrumen cahaya. Oleh sebab itu, orang yang tidak memahami teori cahaya sama sekali, pasti gagal untuk memahami teori filsafat iluminasi, ia pasti gagal menaiki tangga pemahamannya sendiri. (Suhrawardi, 1993, 13) Namun demikian, penulis sama sekali tidak bermaksud menerangkan konsep cahaya dalam filsafat iluminasi secara detil dan terperinci. Mengapa? Karena kajian itu akan membutuhkan pembahasan yang luar biasa panjang dan potensial menggeser fokus kita dari masalah epistemologi. Atas dasar itulah, uraian mengenai konsep cahaya dalam bab ini hanya didasarkan pada kebutuhan urgensif dalam memahami dimensi intuitif dalam epistemologi iluminasi. Dengan kata lain, kita hanya akan membahas konsep cahaya ini, sejauh ia dibutuhkan sebagai elemen penting yang tak mungkin ditinggalkan dalam memahami teori ilmu pengetahuan yang digagas Suhrawardi. Di sinilah letak kesulitan yang sesunguhnya dalam upaya memahami konsep epistemologi iluminasi. Di satu sisi, kita dituntut untuk memahami modus dasar pembangun sistem filsafat ini, yaitu cahaya. Tapi di sisi lain, uraian mengenai cahaya ini sangat luas sehingga tidak menutup kemungkinan malah akan mengalihkan perhatian kita dari kajian utama mengenai konsep ilmu pengetahuan. Jadi, dibutuhkan ketelitian dan kejelian yang luar biasa agar seorang Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 91 peneliti mampu memilah dan memisah antara konsep cahaya yang memang harus diuraikan, dengan yang tidak. Tanpa ketelitian semacam ini, boleh jadi kajian tentang teori ilmu pengetahuan ini akan melebar, tidak efektif, dan takkan memberikan pemahaman yang sempurna. Setelah mengupas tuntas semua masalah yang berkenaan dengan ilmuilmu eksternal yang biasa ia sebut sebagai ilmu hushuli, (ilmu dengan perolehan), Suhrawardi kemudian melangkah lebih jauh dengan menguraikan dimensi lain dari ilmu pengetahuan yang, nilai validitasnya tidak kalah, atau bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan ilmu-ilmu hushuli tersebut. Ia menyebut ilmu ini sebagai ilmu hudhuri, dalam istilah Inggirs, pengetahuan semacam ini biasa diistilahkan dengan knowlegde by presesnt, sedangkan terjemahan bebasnya ke dalam bahasa Indonesia adalah ilmu dengan kehadiran atau pengetahuan dengan kehadiran. Di sinilah sebenarnya letak kegeniusan Suhrawardi sehingga ia disebut sebagai tokoh besar yang sukses memberikan warna baru bagi ilmu pengetahuan. Keberhasilannya menuntun kita menelusuri relung-relung terdalam dalam diri, bukan hanya menyadarkan kita akan kompleksitas dimensi yang terdapat dalam diri kita, lebih jauh lagi, Suhrawardi bisa membuktikan bahwa setiap dimensi itu memiliki medan operasional sendiri dalam ilmu pengetahuan yang, tingkat kebenarannya sama-sama bisa dipertanggungjawabkan. Suhrawardi berhasil memperluas batas wilayah ilmu pengetahuan yang semula hanya terpaku dalam uraian-uraian demonstratif-empiris dan diskursifpredikatif, dengan menghamparkan peta ilmu pengetahuan intuitif-iluminatif. Jika ilmu-ilmu yang tersebut pertama mengandalkan data-data indrawi yang sensible, sedangkan yang tersebut kedua berporos pada objek yang intelligible, maka ilmu yang tersebut terakhir berusaha mengeksplorasi objek yang imaginable. Menurut Suhrawardi, apabila kita mengakui kebenaran ilmu demonstratifempiris dan diskursif-predikatif, berarti tak ada alasan bagi kita untuk mengingkari kebenaran yang berlaku pada ilmu intuitif-demonstratif. Sayangnya, filsafat Barat modern telah terdorong untuk menyingkirkan klaim-klaim kesadaran tertentu dari wilayah pengetahuan manusia, dan menuduhnya sebagai ungkapan gairah atau lompatan-lompatan imajinasi belaka. Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 92 Menurut Hairi Yazdi, hal ini dilakukan agar aliran logika filsafat tidak mengalami kekacauan dan mengakibatkan disintegrasi kesadaran primer. Sebagai contoh, karena pengalaman-pengalaman mistis dicirikan oleh kualitas noetic, dalam artian bahwa pengalaman-pengalaman tersebut membuat klaim tertentu tentang kesadaran terhadap dunia realitas, maka penyelidikan filosofis dipaksa untuk memastikan kebenaran atau kepalsuan pengalaman-pengalaman tersebut sebagai kemungkinan dimensi lain dari akal manusia. Akibatnya, filsafat modern lebih sering mengecam dimasukkannya spesies-spesies pengetahuan ini ke dalam batang tubuh pemikirannya demi mempertahankan keseragaman pemahaman tentang kesadaran. Meskipun demikian, pengabaian pemikiran filosofis terhadap persoalan-persoalan ini, tidaks secara otomatis membuktikan kepalsuan jenis-jenis pengetahuan ini. (Yazdi, 2003, 38) Bagi Suhrawardi, tidak adil jika kita hanya menerima suatu spesies ilmu pengetahuan tertentu, dan menolak spesies yang lain tanpa alasan yang jelas. Selama observasi spiritual ini bisa diterangkan secara cerdas dengan metodologi yang sistematis dan ketat, maka adalah sebuah keniscayaan bagi kita untuk mengakui kebenarannya seperti kita memperlakukan kebenaran yang diperoleh dari refleksi filosofis, atau dari analisa ilmiah. Dalam pembukaan Hikmah alIsyraq, Suhrawardi menulis: ، ﻏ .ﻋﻠﯿﮭﺎ Sebagaimana kita menyaksikan benda-benda empiris, meyakini, dan membangun landasan epistemologis atas keyakinan itu, seperti pada fisika dan disiplin ilmu sejenisnya, maka demikian pula kita menyaksikan fenomena dari dunia spiritual, lalu kita susun kerangka berpikir atas penyaksian itu. (Suhrawardi, 1993, 13) Suhrawardi mengawali kajiannya tentang ilmu hudhuri ini dengan menguraikan hakikat cahaya. Baginya, cahaya adalah sesuatu yang sudah jelas dan terang dengan dirinya sendiri sehingga tidak memerlukan definisi. (Suhrawardi, 1993, 106). Ia menyatakan bahwa cahaya bukan hanya realitas yang paling terang, tapi juga bisa menerangi yang selainnya. Atas dasar itulah, tak ada pengertian apapun yang bisa melukiskan cahaya. Sebab, tujuan pengertian adalah Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 93 membuat sesuatu yang awalnya kabur menjadi benar-benar dipahami. Karena tidak ada yang lebih bisa dipahami dari cahaya, maka secara ipso facto tak ada definisi yang bibutuhkan untuk menerangkan tentang cahaya. Poin yang perlu dicermati di sini adalah, istilah cahaya yang dielaborasi Suhrawardi jangan hanya dipahami secara sempit mengacu kepada cahaya yang kita temui dalam realitas empiris. Dalam konteks yang lebih luas, istilah cahaya ini juga mengacu kepada segala sesuatu yang begitu jelas dan cemerlang sehingga tidak diperlukan penyelidikan praktis apapun untuk menjelaskannya. Bagi orang yang sudah akrab dengan mistisisme Islam, penggunaan terminologi cahaya dalam ranah ilmu pengetahuan sebenarnya bukanlah sesuatu yang asing, dan tidak hanya dilakukan oleh Suhrawardi. Jauh sebelumnya, terminologi semacam ini sudah dilakukan oleh Syaikh Waqi', guru Imam Syafi'i— sang pendiri mazhab fiqih. Dalam sebuah kisah yang sudah populer, diceritakan bahwa Imam Syafi'i mengadukan kesulitannya menghafal kepada gurunya itu. saat itulah, sang guru memberikan jawaban dalam bentuk puisi yang berisi penjelasan bahwa ilmu adalah cahaya, dan hanya akan diberikan Tuhan kepada orang yang hatinya bersih. (Ad-Dimyathi, tt, 167) .ﻓﺄرﺷﺪﻧﻲ إﻟﻰ ﺗﺮك اﻟﻤﻌﺎﺻﻲ .وﻧﻮر اﷲ ﻻ ﯾﮭﺪى ﻟﻠﻌﺎﺻﻲ ﺷﻜﻮت إﻟﻰ وﻗﯿﻊ ﺳﻮء ﺣﻔﻈﻲ وأﺧﺒﺮﻧﻲ ﺑﺄن اﻟﻌﻠﻢ ﻧﻮر Kuadukan kepada Waqi' kesulitanku dalam menghapal Ia menasihatiku untuk meninggalkan maksiat Ia mengatakan bahwa ilmu adalah cahaya Dan cahaya Allah takkan diberikan kepada orang durjana. Setelah menguraikan hakikat cahaya, Suhrawardi meneruskan uraiannya dengan mempertentangkan antara cahaya dengan kegelapan yang dalam terminologinya biasa digunakan istilah nur dan zhalam. Ia membagi masingmasing cahaya dan kegelapan menjadi dua. Dua jenis cahaya itu adalah; [1] Cahaya murni (nur al-mujarrad, nur mahdhi) yaitu cahaya yang asli, tak tercampur, tak inheren dalam sesuatu yang lain, dan mandiri dalam zatnya sendiri. [2] Cahaya temaram (nur al-aridh) yaitu cahaya tidak mandiri, berhajat kepada lokus lain, bersifat aksidental, dan terkandung dalam sesuatu yang lain. (Suhrawardi, 1993, 108) Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 94 Sedangkan dua jenis kegelapan yang dimaksud adalah; [1] Substansi kabur (al-jauhar al-jismani al-ghasiq) yaitu kegelapan yang tidak terdapat dalam sesuatu yang lain dan karenanya murni dan mandiri. Yazdi mencontohkan "materi primer" (hyle) untuk jenis kegelapan jenis ini [2] Substansi gelap (al-hai'ah alzhulmaniyyah) yaitu kegelapan yang terdapat dalam sesuatu yang lain dan tidak mandiri. Yazdi mencontohkan semua objek material yang disebut "aksiden" dalam cara berpikir Plato untuk kegelapan jenis ini. (Suhrawardi, 1993, 109) Lebih lanjut, Suhrawardi mengatakan adanya hal-hal yang tidak termasuk cahaya ataupun kegelapan, tetapi berada di antara keduanya. Mereka disebut objek-objek pertengahan (al-barzakh), misalnya "substansi-substansi material" yang menurut Suhrawardi bukan cahaya ataupun kegelapan, melainkan substansisubstansi yang berada dalam keadaan tertentu sehingga seandainya cahaya terpancar kepada mereka, mereka bisa masuk ke dalam terang, dan dengan demikian menjadi tampak, tetapi seandainya cahaya tidak mencapai mereka, mereka adakan jatuh kembali ke kegelapan mutlak dan lenyap. (Suhrawardi, 1993, 108) Menurut Hairi Yazdi, untuk memudahkan kita dalam menangkap pemikiran Suhrawardi, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyederhanakan pembagian-pembagian di atas dan lebih menganggapnya sebagai penjelasan verbal mengenai istilah teknis belaka. Artinya, perhatian kita jangan sampai tersedot untuk menganalisa dimensi ontologis-metafisik dari istilah-istilah cahaya, kegelapan, dan objek-objek pertengahan, tapi anggaplah semua itu sebagai usaha Suhrawardi dalam mengelaborasi khazanah kekayaan intelektual Persia klasik ke dalam bangunan filsafatnya. Tapi juga bukan berarti kita boleh secara bebas mengangap Suhrawardi telah melakukan elaborasi secara serampangan sehingga elaborasinya itu tak perlu kita pedulikan. Tentu saja, dia sudah sadar dengan konsekuensi metafisik dan religius di balik elaborasinya itu. Oleh sebab itulah, dengan empatik dan apologetik ia membatasi diri pada "permainan bahasa" dualisme ini, dan secara konvensional menyamakan "cahaya" dengan eksistensi, dan makna "kegelapan" dengan ketiadaan. (Yazdi, 2003, 145) Setelah mengetahui istilah-istilah teknis yang diperkenalkan Suhrawardi ini, berarti kita sudah melewati satu tahapan dan bisa melangkah maju untuk Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 95 memasuki tahapan berikutnya dari pemikiran Suhrawardi tentang ilmu pengetahuan. Dan, di sinilah titik krusial itu dimulai. Mengapa? Karena Suhrawardi menyebut setiap orang yang mengetahui dirinya sendiri sebagai "cahaya murni" (nur al-mahdhi). . ﻓﮭﻮ ﻧﻮر ﻣﺤﺾ ﻣﺠﺮد،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻈﻠﻤﺎﻧﯿﺔ Setiap diri yang tidak lalai akan esensinya bukanlah substansi kabur karena penampakan esensinya pada dirinya. Ia juga bentuk kegelapan bagi esensi lain, bahkan bentuk cahaya itu sendiri bukanlah cahaya-bagidirinya.ia adalah cahaya murni. (Suhrawardi, 1993, 110-111) Dalam presmis-premis yang sangat ringkas, ruwet, dikemas dengan katakata aneh serta kalimat yang tidak biasa dalam dunia filsafat ini, ada dua hal yang perlu kita cermati. Pertama, penasbihan setiap orang yang mengetahui dirinya sendiri sebagai cahaya murni. Secara tersirat, Suhrawardi pada dasarnya ingin menegaskan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi cahaya murni yang bukan hanya mampu menerangi dirinya sendiri, tapi juga menerangi alam sekitarnya, tidak hanya menjadi cahaya temaram yang, masih membuthkan cahaya lain supaya bisa menerangi dirinya sendiri. Jika ditarik dalam lapangan praktis, kita bisa menafsirkannya dengan, setiap individu adalah entitas unik yang memiliki "bekal" sama dan setara untuk memiliki ilmu pengetahuan yang berguna bagi dirinya sendiri dan orang lain. Sayangnya, tidak semua individu menginsafi potensi yang sudah tertanam dalam dirinya itu sehingga bisa dieksploitasi sedemikian rupa. Akibatnya, potensi itu statis dan tidak mewujud menjadi aktus yang bisa dimanfaatkan, walaupun tidak hilang sama sekali. Kondisi seperti ini disinyalir Suhrawardi pada kalimat pembukaannya dalam premis di atas, "setiap diri yang tidak lalai akan esensinya." Kalimat ini sebenarnya bisa diartikan sebagai pengelompokan manusia menurut Suhrawardi yang, secara sederhana bisa dibagi dua. Yaitu orang yang menyadari potensi dirinya lalu mengeksplorasinya, dan orang yang tidak menyadari potensi dirinya sehingga tidak bisa berbuat apa-apa terhadap potensi yang dimiliki tersebut. Kelompok yang tersebut pertama ia istilahkan sebagai nur Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 96 al-mujarrad (cahaya murni), sedangkan kelompok yang tersebut terakhir ia sebut sebagai nur al-aridh (cahaya temaram). Kedua, kesadaran diri adalah masalah penting dalam ilmu pengetahuan, bahkan ia—dalam terminologi ilmu hudhuri—merupakan bagian dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Suhrawardi melangkah maju kepada masalah pengetahuan diri dengan mengatakannya bahwa pengetahuan ini identik dengan realitas diri itu sendiri, dan realitas diri dengan cahaya murni. Karena itu, realitas diri berlaku sebagai contoh utama dalam ilmu hudhuri yang, dalam terminologi Suhrawardi, merupakan cahaya murni yang tak ada apapun yang lebih nyata darinya. Pengetahuan diri ini juga menjadi elemen khusus yang oleh Hairi Yazdi disebut sebagai modus utama dalam epistemologi ilmuninasi. Untuk kepentingan teknis, penulis akan memisahkan uraian mengenai masalah ini dalam sub bab lain, walaupun sebenarnya ia adalah bagian yang sangat terkait dengan konsep cahaya, dan bahkan dalam sejumlah kesempatan, ia disebut sebagai cahaya itu sendiri oleh Suhrawardi. Di samping itu, penulis juga akan memberikan sentuhan-sentuhan sufistik serta sedikit perbandingan dengan teori filsafat klasik dan modern yang memiliki relevansi sebagai tambahan informasi untuk mempermudah proses pemahaman kita, sekaligus sebagai contoh nyata dari bentuk ilmu hudhuri itu sendiri. Pada titik-titik tertentu, sentuhan sufistik dan studi banding ini bisa memberikan penjelasan bagi kita mengenai salah satu langgam yang digunakan Suhrawardi untuk membangun konsep filsafatnya, sebagaimana yang ia akui sendiri dan telah diterangkan di bab 2. 5.2 Pengetahuan Diri Suhrawardi meyakini bahwa, langkah pertama yang wajib dilakukan oleh setiap insan sebelum mengetahui yang lain adalah, mengetahui dirinya sendiri. Mereka harus bisa menjawab pertanyaan "Bagaimana sesungguhnya kita mengetahui diri kita?" Apakah hakikat jenis pengetahuan yang umumnya dikenal sebagai "pengetahuan diri" atau "kesadaran diri?" apakah sama dengan mengetahui meja, kursi, bulan, atau matahari? Atau, barangkali esensi Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 97 pengetahuan diri harus dipandang berbeda, tidak hanya sebagian, tetapi seluruhnya, dari esensi pengetahuan yang lain? Eksistensi diri saya pasti dipraanggapkan dalam setiap proposisi atau tindakan yang di dalamnya saya adalah subjek, atau yang untuknya saya bertanggung jawab? Inilah pertanyaanpertanyaan fundamental bagi filsafat iluminasi tentang pengetahuan diri dalam teori Suhrawardi tentang ilmu hudhuri. Dalam lintasan sejarah, urgensi mengetahui diri ini sudah ditekankan oleh Sokrates melalui ungkapannya yang sangat terkenal "Gnothi se auton" (Kenali dirimu sendiri). Melalui kalimat singkat yang menjadi dasar dari seluruh pemikiran filsafatnya ini, Sokrates menghimbau manusia untuk mengenali hakikat dirinya terlebih dahulu, sebelum berusaha mencari pengetahuan faktual-etis yang lain. Slogan ini demikian populer sehingga orang-orang Yunani menuliskannya di kuil dewa-dewi mereka. (Bagus, 2002, 281) Dalam dunia Islam, masalah pengetahuan diri juga menduduki posisi agung karena diyakini sebagai pilar utama untuk mengetahui Tuhan. Sekadar catatan, pengetahuan tentang Tuhan ini jangan dimaknai sebagai pengetahuan tentang esensi-Nya. Sebab, manusia tidak mungkin mengetahui esensi Tuhan, dan hanya Dia sendirilah yang mengetahui esensi diri-Nya. (Amstrong, 1995, 134). Pengetahuan tentang Tuhan ini harus dimaknai sebagai pengetahuan primordial nan unik. Primordial karena ia merupakan pengetahuan yang, bukan hanya bisa mengantarkan manusia pada kedudukan spiritual tertinggi, tapi juga mampu menghadirkan kedamaian dan ketenangan dalam jiwa. Dan, unik karena sepanjang sejarah pergulatan kaum sufi dengan pengetahuan ini, tak satu pun di antara mereka yang bisa memaparkan pengetahuan ini secara subtil setelah mengalaminya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menguraikan sejumlah langkah yang bisa ditempuh untuk bisa mencapai pengetahuan ini. Tapi satu hal yang pasti, geliat kaum sufi mendalami pengetahuan ini karena dimotifasi oleh hadis maudhu' yang berbunyi: . أﻋﺮﻓﻜﻢ ﺑﻨﻔﺴﮫ أﻋﺮﻓﻜﻢ ﺑﺮﺑﮫ.ﻣﻦ ﻋﺮف ﻧﻔﺴﮫ ﻋﺮف رﺑﮫ Orang yang mengetahui dirinya, pasti mengetahui Tuhannya. Orang yang paling mengetahui dirinya di antara kalian, adalah orang yang paling mengetahui Tuhannya. (Ar-Rifa'i, 1408, 48) Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 98 Masalah ini nampaknya disadari betul oleh Suhrawardi sehingga ia, senada dengan Sokrates, dalam karyanya yang berjudul al-Masyari' wa al-Mutharahat menyatakan bahwa manusia seyogianya mencari pengetahuan tentang esensi dirinya sendiri, sebelum melangkah pada pengetahuan yang lebih jauh. (Suhrawardi, 1993, 484) Maksud dari mengetahui diri di sini adalah mengetahui esensi diri yang terminologi Suhrawardi dan filsafat Islam lazim disebut sebagai anaiyyah atau keakuan, sedangkan dalam terminologi filsafat Barat biasa disebut dengan aku performatif. Untuk memudahkan kajian, penulis selanjutnya hanya akan menggunakan satu istilah, yaitu aku performatif. "Aku performatif" ini adalah subjek "aku" yang asli, primer, dan langsung yang aktif serta hadir dalam segenap tindakan, termasuk tindak mengetahui. Ia bukan "aku" yang direnungkan, dikonsepsi, direpresentasikan. Bukan pula "aku" yang ditindak, dihadirkan, atau ditunjuk. Ia benar-benar subjek yang telanjang, hadir, serta imanen dalam seluruh tindakan fenomenal, dan merupakan subjek aktif yang berpikir, berbicara, dan bertindak. Guna memudahkan pemahaman kita tentang konsep aku performatif yang benar-benar menjadi subjek sejati dan bukan yang dikonsepsi ini ada baiknya jika kita menggunakan pemikiran John Langshaw Austin (1911-1960) tentang performative utterances (ungkapan-ungkapan performatif) dan constantive utterances (ungkapan-ungkapan konstanstif). Menurutnya, pernyataan-pernyataan seperti "Aku melihat Pak X duduk" "Aku makan nasi" atau "Aku membaca buku". berbeda dengan pernyataan-pernyataan semisal "Aku berjanji mengirim uang" "Aku berterima kasih kepadamu" atau "Aku memohon ampun kepada-Mu." Tiga contoh statemen pertama, menurut Austin, disebut sebagai constantive utterances karena berfungsi untuk menggambarkan, melaporkan, atau menginformasikan suatu keadaan faktual bahwa; aku berjanji, aku berterima kasih, atau aku memohon ampun. Ada sesuatu yang dinyatakan, dilukiskan, atau dikonstatasi dalam kalimat-kalimat tersebut. Sedangkan tiga contoh statemen terakhir disebut sebagai performative utterances karena sama sekali tidak bermaksud melaporkan atau melukiskan sesuatu, akan tetapi merupakan tindakan itu sendiri. Ada sesuatu yang terjadi oleh Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 99 karena kalimat tersebut. Jelasnya, pernyataan "Aku berjanji" tidak melaporkan suatu tindakan berjanji, tetapi ia adalah tindakan berjanji itu sendiri. Pernyataan "Aku berterima kasih" bukan dimaksudkan untuk menggambarkan tindakan berterima kasih, namun ia merupakan tindakan berterima kasih itu sendiri. (Bertens, 2002, 60-67) Dalam ungkapan performatif, "aku" yang berbicara adalah identik dengan "aku" yang bertindak. Statemen "Aku berjanji" adalah tindakan "aku", bukan suatu informasi tentang "aku". Dalam konteks epistemologi Suhrawardi, aku performatif adalah aku yang identik dengan tindak mengetahui. Tidak ada dualitas subjek-objek, dan tidak ada pula konseptualisasi, introspeksi, atau representasi tentang "aku". Sebab, jika "aku" dikonsepsi atau direpresentasi, "aku" itu bukan lagi aku performatif atau aku yang sejati, tapi "sesuatu yang lain" yang dianggap sebagai "aku". Disadari atau tidak, sampai saat ini kata "aku" yang merupakan kata kunci dalam pengenalan diri tetap menjadi sebuah problem akut dalam dunia filsafat. Ia implisit hadir dalam setiap tindak mengetahui, perbuatan, dan tindak bahasa manusia. Anehnya, ia tidak bisa ditunjuk. Karena apabila ditunjuk, ditindak, atau dinilai, ia tidak lagi berperan sebagai "aku", tetapi "dia" atau aku fiktif. Dalam upaya menyelesaikan problem ini, kita akan tahu betapa Suhrawardi jauh lebih matang daripada Rene Deskartes (1596-1650) kendati tokoh iluminasi itu hidup lebih dulu, serta memiliki waktu yang jauh lebih pendek untuk menuntaskan persoalan filosofis tentang pengetahuan diri dibanding Deskartes yang sangat popupler sebagai bapak filsafat modern, melalui salah satu metodenya yang terkenal dengan metode kesangsian atau keraguan (Cartesian Doubt) yang tersimpul dalam kalimat cogito ergo sum. Seperti telah diketahi bersama, setelah dirisaukan oleh skeptisisme filosofis, Deskartes sampai pada satu titik di mana dia menemukan dirinya tak lagi rentan terhadap keraguan. Dengan memusatkan pada prinsipnya yang tak teragukan lagi, cogito. Dengan kata lain, kepastian eksistensi keraguan saya membawa kepada kepastian mengenai eksistensi diri saya. Jadi, Deskartes sebenarnya hendak menegakkan pengetahuan mengenai kediriannya melalui kepastian dirinya berkenaan dengan keadaan ragu. Dia menyuguhkan satu tindak Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 100 fenomenal pikirannya sebagai bukti untuk menjelaskan kebenaran eksistensi identitas personalnya. Melalui prinsip "Aku berpikir, maka aku ada" Deskartes menunjukkan bahwa rasionalitas representatif sang subjek terlebih dahulu daripada realitas eksistensi, termasuk eksistensi dirinya sendiri. Menurutnya, kesadaran bahwa "aku ada" muncul belakangan setelah "aku sadar bahwa aku berpikir". Ia mengemukakan doktrin ini melalui argumen metode kesangsian bahwa, segala sesuatu boleh disangsikan kebenarannya, kecuali kesadaran akan keraguan itu sendiri. Suatu aktivitas yang menunjukkan aktvitas berpikir. Dari doktrin ini, bisa disimpulkan bahwa menurut Deskartes, subjek "aku ada" adalah produk representasi dari subjek "Aku berpikir. Doktrin ini menimbulkan masalah baru karena eksistensi subjek ditempatkan sebagai objek aktivitas berpikir yang representatif-fenomenal, sehingga bisa juga dipahami bahwa subjek "aku ada" sama dengan "aku yang diobjekkan" atau "aku representatif". Dengan demikian, konsekuensi selanjutnya adalah, kita bisa mengatakan bahwa Deskartes sejatinya tidak merujuk kepada realitas eksistensial manapun, kecuali apa yang ia bayangkan sebagai "aku ada". Jadi, jika kita boleh menyebut apa yang dirujuk Deskartes itu sebagai "aku ilutif", maka adagium pembentuk Zeitgeist (ruh zaman) modern itu menjadi berbunyi, "Aku berpikir, maka aku ilutif ada." Hal ini terjadi karena dengan menjadikan berpikir sebagai cara untuk mengetahui diri, sama seperti menjadikan tindakan baik yang bersifat intelektual seperti berpikir, ataupun fisik seperti membaca sebagai modus untuk menyadari eksistensi diri. Dalam bahasa yang sederhana, pengetahuan saya mengenai tindakan saya berfungsi sebagai sebab bagi pengetahuan saya tentang diri saya. Konsekuensinya, akan terkesan bahwa seseorang harus mengeluarkan "dirinya" dari "dirinya" supaya bisa menjadi saksi atas dirinya sendiri. Titik krusial inilah yang sangat disadari oleh Suhrawardi sehingga ia bisa mengantisipasinya secara indah. Menurutnya, manusia mengetahui dirinya tidak melalui representasi dirinya. Dalam Hikmah al-Isyraq dengan akurat dia menulis: Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 101 ! وھﻮ ﻣﺤﺎل، وأن ﯾﻜﻮن إدراك ذاﺗﮭﺎ ﺑﻌﯿﻨﮫ إدراك ﻏﯿﺮھﺎ،ھﻮ Sesuatu yang eksis dalam dan sadar akan dirinya sendiri tidak mengetahui dirinya melalui representasi atas dirinya yang tampak oleh dirinya. Sebab, jika seseorang harus membuat representasi dirinya untuk mengetahui dirinya, representasi itu adalah "dia" dalam kaitannya dengan diriku, dan bukan "aku". Ini karena representasi keakuan tidak pernah menjadi realitas diri "keakuan" tersebut. Dengan demikian, hal yang muncul dalam kesadaran adalah representasi itu. Jadi, dapat dikatakan bahwa kesadaran akan "keakuan" akan menjadi kesadaran akan "kediaan", dan bahwa kesadaran akan realitas keakuan karenanya akan menjadi kesadaran akan apa yang bukan "keakuan". Dan, ini absurd! (Suhrawardi, 1993, 111) Dari argumen pelik dan berbelit ini, kita bisa memahami bahwa konsep pengetahuan diri yang dikembangkan Suhrawardi bersifat performatif sekaligus swaobjektif. Performatif karena "aku" yang ingin diketahui adalah aku yang subjektif, bukan "aku" yang ditunjuk, dikonsepsi, apalagi diobjektifikasi. Dan swaobjektif, karena pengetahuan ini bersifat mandiri tanpa representasi yang bisa dirujuk seperti yang berlaku dalam tataran korenspondensi. Dan, faktor inilah yang kemudian membuat ilmu hudhuri disebut sebagai ilmu yang swaobjek. Setelah berhasil mengajukan argumen yang bersifat metafisik dengan mengingkari pengetahuan diri diperoleh melalui pengetahuai tentang citra atau representasi seperti di atas, Suhrawardi melangkah maju dengan menguratakan bahwa manusia juga tidak mengetahui dirinya melalui pelbagai atribut yang melekat atau bahkan identik dengan dirinya. Masih dalam buku dan paragraf yang sama, ia menulis: . . .ﺑﺎﻟﺼﻔﺎت اﻟﺰاﺋﺪة Tak bisa dibayangkan bahwa seseorang mengetahui dirinya melalui sesuatu yang ditambahkan pada dirinya, karena tambahan itu akan berlaku sebagai atribut bagi dirinya. Jika demikian halnya, dia memutuskan bahwa setiap atribut yang diasosiasikan dengan realitas dirinya, adalah milik realitas dirinya sendiri dan dengan demikian tersirat bahwa dia telah mengetahui dirinya sendiri sebelum mengetahui atau bahkan tanpa atributatribut ini. Jadi, seseorang tidaklah mengetahui dirinya sendiri melalui atribut-atribut yang ditambahkan padanya. (Suhrawardi, 1993, 111) Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 102 Dalam karya lainnya yang berjudul al-Talwihat, Suhrawardi secara lebih spesifik mengukuhkan statemen di atas dengan menyatakan bahwa manusia tidak mengetahui dirinya melalui organ-organ tubuhnya sendiri. Dengan tandas ia menyatakan, jika seseorang mempostulatkan dalam pikiran bahwa seorang manusia yang secara tiba-tiba diciptakan dalam kondisi sempurna, tanpa anggota badan atau persepsi indrawi, manusia ini takkan menyadari sesuatu kecuali "kediriannya" sendiri. Bagi Suhrawardi, mustahil seseorang terisolasi dari diri dan pengenalan atas dirinya sendiri. Alasannya, tak ada sesuatu yang lebih nyata bagi seseorang selain kediriannya sendiri, sehingga untuk mengenalnya, ia cukup membutuhkan dirinya sendiri, dan tidak membutuhkan pelbagai atribut dan objek eksternal lainnya. Dengan kata lain, pengenalan diri ini berlangsung secara otomatis, konstan, dan simultan. Kebenaran hipotesa Suhrawardi ini belakangan sudah banyak diakui oleh para filsuf, salah satunya adalah Santo Agustinus. Senada dengan Suhrawardi, Agustinus juga melihat pengetahuan diri atau "keakuan performatif" sebagai bentuk pencapaian ontologis yang paling dekat dan innate dari kesadaran manusia. Dalam retorikanya yang sangat terkenal, ia pernah berkata, "Quid autem propinguius meipsomihi?" (Masih adakah sesuatu yang lebih tampak bagiku selain diriku sendiri?). Pengetahuan seperti ini tidak mengandaikan adanya jarak atau distansiasi antara "keakuan performatif" dan diri. Sebuah pandangan yang berbeda dari fenomenologi modern yang melihat pengetahuan atau kesadaran semacam ini sebagai cerminan dari distansiasi yang tak terelakkan setiap kali subjek menyadari keberadaan dirinya. Tentang masalah ini, Suhrawardi menulis dalam Hikmah al-Isyraq pasal ke-116: وإذ. .اﻟﻈﺎھﺮة ﻟﻨﻔﺴﮭﺎ أو اﻟﻐﯿﺮ اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﮭﺎ Mustahil Anda terisolasi dari diri dan pengenalan atas diri Anda. Karena pengenalan itu tidak terjadi berkat representasi atau atribut, maka untuk mengenali diri, Anda hanya membutuhkan diri Anda yang nyata dan tidak pernah absen dari Anda. (Suhrawardi, 1993, 112) Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 103 Berdasarkan kutipan singkat di atas, kita bisa mengetahui dengan jelas dua argumen dasar yang digunakan Suhrawardi dalam memetakan pengetahuan diri. Argumen pertama yang diajukan Suhrawardi berkaitan dengan fungsi logis, epistemik, dan semantik dari "keakuan" yang dikontraskan dengan "kediaan". Sedangkan argumen kedua berkenaan dengan distingsi antara atribut-atribut yang kepadanya atribut-atribut ini dilekatkan, yang secara prospektif dianggap sebagai realitas kedirian. Meskipun argumen ini secara tegas menyerukan perbedaan antara atributatribut dan diri yang, kepada atribut-atribut ini ditujukan, Suhrawardi tetap mengemukakannya dengan bahasa yang akrobatik sehingga bahkan pembedaan ini mesti dibuat oleh subjek performatif itu sendiri, bukan oleh pelaku di luar dirinya. Hal ini ia lakukan karena ingin bersikap konsisten dan tidak jatuh pada pertimbangan dualitas "aku" seperti yang terjadi dalam permikiran Deskartes. Konsistensi ini sangat penting karena penilaian dari luar yang membedakan atribut-atribut dengan pemilik atribut itu, rentan terhadap konsekuensi memperlakukan diri sebagai objek yang, karena diubah menjadi "dia", bisa dengan mudah dianalisis menjadi kualitas-kualitas dari sesuatu yang dikualifikasi. Dengan membangun argumen secara negatif tentang pengetahuan diri— yaitu mengingkari pengetahuan manusia diperoleh dengan mengetahui representasi dirinya, atribut, dan bahkan organ tubuhnya sendiri, Suhrawardi hakikatnya ingin mengatakan bahwa "aku performatif" dalam epistemologi iluminasi ini benar-benar mengacu kepada subjek yang eksis dalam dirinya sendiri, bukan dalam yang lain, memiliki kemampuan untuk mengetahui dirinya sendiri. Dialah subjek yang berbicara, bertindak, serta membuat penilaian terhadap sesuatu yang disadarinya. "Aku performatif" yang tak bisa diubah dari subjek yang mengetahui menjadi subjek tak bernyawa yang bisa dirujuk sebagai "dia". Subjek yang mengetahui dirinya oleh dan dengan dirinya sendiri secara murni tanpa sarana apapun. Dari titik inilah Suhrawardi kemudian mengembangkan teori epistemogi ilmu hudhuri yang sangat unik dan berbeda dari ragam epistemolgi yang lain. Suatu epistemologi yang dicirikan dengan kesatuan eksistensial antara tiga modus pengetahuan yang meliputi: [1] Subjek yang mengetahui. [2] Objek yang Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 104 diketahu. [3] Tindak mengetahui. Tentang hal ini, komentator Suhrawardi yang paling masyhur, Syamsuddin Muhammad al-Syahrazuri menulis dalam Syarh Hikmah al-Isyraq: . .واﻟﻤﻌﻘﻮل واﺣﺪ Setiap individu yang mengetahui dirinya adalah cahaya murni. Setiap cahaya murni adalah terang bagi dan menyinari dirinya sendiri. Konsekuensinya, subjek yang mengetahui, objek yang diketahui, tindak mengetahui di sini adalah satu. Sama seperti pikiran, pemikir, serta sesuatu yang dipikirkan itu adalah satu. (Syahrazuri, 1993, 301) Artinya, pengetahuan diri ini dijadikan sebagai instrumen yang paling dasar oleh Suhrawardi dalam konsep pengetahuan dengan kesadaran. Sekaligus dimensi yang paling elementer dari setiap tindak mengetahui. Dengan kata lain, mengetahui berarti menyatakan adanya suatu unifikasi eksistensial antara subjek yang mengetahui (pikiran) dengan objek yang diketahui (realitas atau bendabenda), sehingga kehadiran objek bisa dikenali secara meyakinkan. Dengan mengikuti aksioma Aristotelian, berarti dapat dinyatakan bahwa subjek atau pikiran yang mengetahui dan objek yang diketahui adalah identik. Dalam bahasa latin biasa diungkapkan dengan kalimat Idem est et intellectus et intellectum, sedangkan dalam bahasa Arab biasa dilafalkan dengan Ittihad al-aqil wa alma'qul (Kesatuan antara pemikir dan yang dipikirkan). Dalam epistemologi ini, pengenalan atas objek tidak selalu dijalani dengan bantuan representasi atau gambaran objek yang terpantul pada pengindraan subjek. Pengenalan semacam inilah yang berlaku dalam pengetahuan swaobjek. Sebuah modus pengetahuan yang, ketika objek sudah berhasil dikenali, maka tidak lagi dibutuhkan kata, bahasa, atau satuan proposisi. Mengapa? Karena pengetahuan tentang objek tersebut hadir begitu saja dan mewujud dalam kesadaran. Sebagai dasar dari epistemologi ini, kesadaran atau pengetahuan diri tentu menjadi kondisi yang paling ultim. Kondisi ini ditandai dengan terjadinya penampakan maksimal atas realitas diri dan kesadaran sepenuhnya atas dimensi ontologis subjek yang berpusat pada keakuan "I-ness." Keakuan ini bisa Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 105 didefinisikan sebagai keterpusatan eksistensial subjek pada kehadiran dirinya di tengah fenomena objek-objek. Karena subjek hadir untuk dirinya dan mengalami pengetahuan atas dirinya, maka terdapat wilayah kediaan "It-ness" di luar subjek, yang berada di luar realitas faktual dan status ontologis subjek. Dengan "kediaan" ini, subjek menegaskan kehadiran dirinya dan memastikan adanya medan lain yang tidak dihadirinya. Ketidak-hadiran subjek atas medan tersebut bukanlah aspek negatif dari "keakuan", tetapi lebih disebabkan untuk menjaga totalitas eksistensinya dan menegakkan hubungan korelatif dan keserentakan dengan "kediaan". Dengan teori korelativitas ini, Suhrawardi berhasil menempatkan subjek-objek dalam keserentakan potensi dan aksi, sehingga dengan begitu, relasi keakuan-kediaan berlangsung dalam keseimbangan, meskipun tetap saja tidak dapat saling dipertukarkan (inkonvertibilitas) atau dipergantikan (invariabilitas) begitu saja. 5.3 Tahapan Memperoleh Ilmu Hudhuri Seperti banyak disinggung di muka bahwa filsafat iluminasi dengan konsep ilmu hudhurinya diperoleh dari sintesa elegan dari pelbagai kebijaksaan klasik pra Suhrawardi, khususnya antara olah pikir dalam filsafat diskursif (hikmah al-bahtsiyah) dan olah rasa dalam filsafat intuitif (hikmah al-dzauqiyah). Sintesa semacam ini, tentu saja bukan pekerjaan mudah yang bisa dilakukan secara serampangan dengan mengambil salah satu unsur tertentu dari semua corak filsafat yang ditemui Suhrawardi, untuk kemudian dilebur dalam suatu wadah yang bernama filsafat iluminasi. Sintesa yang dilakukan secara sembarangan bukan hanya sangat mungkin menghasilkan suatu pemikiran yang kacau, alih-alih malah membuahkan suatu teori sesat yang tak bisa dipertanggungjawabkan! Sebagai perumpamaan, jika Anda bukan ahli farmasi yang memiliki pengetahuan mendalam tentang kandungan kimia dalam obat-obatan, maka jangan pernah berspekulasi meracik ramuan tertentu dari pelbagai obat yang Anda miliki dengan harapan akan memperoleh obat mujarab yang bisa menyembuhkan beragam penyakit. Sebab, hasil ramuan Anda bukan tidak mungkin malah menjadi racun mematikan yang sangat berbahaya. Selain dibutuhkan pengetahuan yang mendalam terhadap kandungan kimiawi sejumlah obat, hasil racikan Anda wajib Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 106 lulus serangkaian pengujian laboratorium sebelum dinyatakan sebagai ramuan mujarab yang benar-benar manjur dan bisa dipergunakan semua orang. Hukum yang sama juga berlaku dan sudah dipraktikkan oleh Suhrawardi saat menggagas pemikiran-pemikirannya. Nampaknya ia sangat menyadari bahwa suatu gagasan hampir sama dengan obat yang, sebelum dilemparkan kepada konsumen secara luas, harus melewati uji kelayakan terlebih dahulu. Oleh sebab itulah, sebelum ia menuangkan konsep filsafat iluminasi dengan segenap lingkup bahasannya yang beragam, terlebih dahulu ia sudah mendiskusikan konsepkonsepnya itu dengan murid-muridnya. Walaupun tidak ada penjelasan yang pasti tentang hal ini, namun kita bisa menangkapnya secara tersirat dari keterangan seputar latar belakang penulisan karya utamanya yang berjudul Hikmah al-Isyraq. Dalam mukaddimah Hikmah al-Isyraq, terdapat keterangan yang menunjukkan bahwa filsafat ini pada dasarnya sudah diajarkan melalui lisan oleh Suhrawardi terhadap murid-muridnya. Merekalah yang kemudian mendesak sang guru agar menuangkan ajaran-ajarannya itu ke dalam bentuk tulisan. Akhirnya, setelah berhasil menerabas berbagai kesulitan yang dihadapi, Suhrawardi berhasil menulis karya besarnya tersebut. . . .أﻛﺘﺐ ﻟﻜﻢ ﻛﺘﺎﺑﺎ أذﻛﺮ ﻓﯿﮫ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻟﻲ ﺑﺎﻟﺬوق ﻓﻲ ﺧﻠﻮﺗﻲ وﻣﻨﺎزﻟﺘﻲ Ketahuilah saudara-saudaraku, besarnya desakan kalian agar aku menuliskan filsafat iluminasi, telah menggoyahkan tekadku untuk menolak dan membuatku tidak bisa mengelak. Jika bukan karena kebenaran yang pasti dari pesan yang ada, serta perintah yang datang dari suatu tempat yang meniscayakan terjadi, saya takkan memiliki motivasi kuat untuk mewujudkannya. Sebab, ada kesulitan besar yang tidak kalian sadari. Namun kalian, saudara-saudaraku—semoga Allah menunjukkan kalian pada apa yang Dia cintai dan Dia ridhai—terus mendesakku untuk menulis sebuah karya yang berisi pengalaman yang kuperoleh melalui intuisi selama masa-masa khalwat dan kontemplasi. (Suhrawardi, 1993, 9) Jika kita cermati kalimat-kalimat di atas secara teliti dan tidak terfokus pada faktor yang melatari Suhrawardi menulis karyanya tersebut, khususnya pada Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 107 rangkaian kalimat terakhir, kita akan menemukan paparan spesifik yang berkaitan langsung, sekaligus menjadi alasan kuat mengapa sub-bab ini menjadi sangat penting. Persisnya, dari mana dan bagaimana Suhrawardi mendapatkan gagasan tentang filsafat iluminasi serta ilmu hudhuri. Kajian ini menjadi vital mengingat meskipun secara sepintas teori filsafat iluminasi dihasilkan dari kombinasi pelbagai filsafat sebelumnya, namun ternyata Suhrawardi tidak secara mudah mengambil bagian-bagian tertentu dari suatu pemikiran filsafat dan membuang sebagian yang lain, supaya bisa disintesakan secara indah dalam gagasan besarnya. Lebih-lebih kenyataan membuktikan bahwa, meskipun dalam sejumlah tulisannya ia secara tegas menyerang pemikiran diskursif, filsafatnya tidak secara bernas lahir dari ketidakpuasan terhadap teori filsafat tersebut. Jadi, teori filsafat Suhrawardi bukanlah sebuah bentuk perlawanan sengit terhadap teori filsafat peripatetik. Sebagai bukti, sejumlah unsur filsafat diskursif tetap ia lestarikan dalam filsafat iluminasi. Dengan demikian, filsafat iluminasi tidak berbeda secara kontras dengan filsafat peripatetik. Hal ini berbeda dengan Aristoteles misalnya, yang karena tidak puas terhadap pengetahuan sejati dan konsep dunia idea Plato, ia kemudian berusaha membuktikan bahwa sumber pengetahuan adalah realitas empiris, sehingga pengetahuan sejati adalah pengetahuan yang dihasilkan dari pengamatan terhadap benda-benda empiris, bukan terhadap dunia idea. Fakta lain yang juga menarik adalah, meskipun Suhrawardi terus terang mengagumi pemikiran Plato dan Aristoteles dan menyatakan bahwa teori filsafat yang ia paparkan juga diambil dari konsep dari kedua pemikir Yunani tersebut, ternyata untuk mendapatkan suatu konsep yang utuh tentang filsafat iluminasi, ia menggunakan suatu metode unik. Metode itu ia paparkan dalam mukaddimah Hikmah al-Isyraq sebagai berikut: . ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺸﻜﻜﻨﻲ ﻓﯿﮫ ﻣﺸﻜﻚ، ﺧﺘﻰ ﻟﻮ ﻗﻄﻌﺖ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺨﺤﺔ ﻣﺜﻼ،اﻟﺤﺠﺔ Semula, (pengetahuan) ini tidak kuperoleh melalui pemikiran, tapi melalui sumber lain. Aku pun lantas mencari argumentasinya. Sehingga ketika argumentasinya sudah valid, tak seorang pun dapat menggoyahkanku untuk meragukannya. (Suhrawardi, 1993, 10) Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 108 Dari paparan ini, kita tahu bahwa konsep filsafat iluminasi tidak diperoleh melalui penalaran dan pemikiran, akan tetapi diperoleh melalui mekanisme yang berlaku dalam ilmu hudhuri sendiri. Dalam hal ini, nampaknya Suhrawardi ingin konsisten dengan gagasannya sendiri tentang konsep epistemologinya yang unik tersebut, sekaligus ingin membuktikan bahwa hanya dengan epistemologi hudhuri, suatu konsep dan gagasan baru yang original benar-benar bisa dihasilkan. Walaupun tidak dinyatakan secara tegas, namun kita bisa menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan kalimat "sumber lain" dalam kutipan di atas adalah intuisi yang didapatkan setelah melakukan serangkaian kontemplasi sebagaimana ia sebutkan dalam kutipan sebelumnya. Atas dasar itulah, rasanya tidak absurd bagi kita untuk mencoba metode yang diusulkan Suhrawardi jika kita ingin mendapatkan ilmu pengetahuan baru, walaupun metode tersebut tetap bukan satusatunya cara yang bisa diempuh, dan masih banyak cara lain untuk digunakan. Namun jika berkaca pada fakta sejarah yang menunjukkan bahwa pemikiran filsafat di dunia Islam tidaklah semarak seperti yang berlangsung di Barat, mungkin sekarang sudah saatnya bagi kita untuk mempertimbangan solusi yang ditawarkan Suhrawardi secara serius. Pada mukaddimah kitab al-Masyari' wa al-Mutharahat yang kemudian diulangi lagi pada penutup kitab Hikmah al-Isyraq, menurut Suhrawardi, ada tiga tahap yang harus dilalui dalam upaya mendapatkan pengetahuan sejati yang tersimpul dalam ilmu hudhuri. Pertama adalah tahap persiapan. Pada tahap ini seorang pencari kebenaran harus melakukan sejumlah aktivitas penting yang bisa mengantarkannya pada tahap berikutnya. Uniknya adalah, rangkaian aktivitas pada tahap ini sangat jauh dari kesan-kesan akademis semisal melakukan kajian terhadap pemikiranpemikiran tertentu, mengadakan penelitian terhadap konsep-konsep tertentu, atau bahkan melakukan pengujian terhadap teori-teori tertentu. Menurut Suhrawardi dalam pengantar al-Masyari' wa al-Mutharahat, aktivitas pada tahap ini adalah menjauhi kesenangan duniawi. (Suhrawardi, 1993, 195) Keterangan yang lebih rinci mengenai bentuk "menjauhi kesenangan duniawi" ini bisa kita peroleh dalam bagian penutup Hikmah al-Isyraq yang meliputi; mengasingkan diri selama empat puluh hari, berhenti mengonsumsi Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 109 daging, mengurangi konsumsi makanan, merenungkan dan mengkontemplasikan cahaya Tuhan, serta melakukan semua perintah-Nya. (Suhrawari, 1993, 258) Aktivitas seperti ini, menurut Hossein Ziai sangat mirip dengan poa hidup asketik dan mistik yang marak di zaman Shurawardi, walaupun tidak sama persis dan tidak seketat seperti yang dilakukan oleh para sufi pada masanya. Pada titik ini, kita bisa melihat besarnya pengaruh ritual-ritual sufisme yang memang mewarnai kehidupan sekaligus menjadi ciri khas corak keberagamaan pada abadabad tersebut. Sebagaimana laporan sejarah, ilmuwan Muslim klasik dalam segala bidang rata-rata menjalani hidup secara zuhud dan asketik jauh dari gelimang harta duniawi, hatta yang dekat dengan kekuasaan dan tinggal di lingkungan istama. Catatan penting yang harus penulis utarakan berkaitan dengan pembabakan tahapan—khususnya tahapan yang pertama—untuk memperoleh ilmu hudhuri ini adalah, jangan pernah beranggapan cara memperoleh pengetahuan jenis ini cukup dengan melakukan olah intuisi spiritual serta menjalankan praktik hidup asketik saja, kemudian mengabaikan proses edukasi dan instrumen studi ilmiah lainnya. Anggapan seperti ini adalah kesalahan besar yang takkan membuahkan apa-apa. Kita harus ingat dan melihat lagi bab 2 kajian ini yang menerangkan bahwa Suhrawardi adalah sosok terpelajar yang, karena besarnya rasa cinta terhadap ilmu pengetahuan, ia bukan saja harus rela menemupuh kesulitan berpindah dari suatu kota ke kota yang lain untuk menuntut ilmu dari guru-guru yang tersohor, tapi juga berusaha sekuat tenaga untuk menelusuri suatu pengetahuan hingga ke sumbernya yang paling radikal. Oleh sebab itu, bisa kita asumsikan bahwa sebelum merumuskan tahapantahapan ini, Suhrawardi sebelumnya sudah melakukan studi yang mendalam terhadap pelbagai pemikiran dan teori filsafat sehingga penguasaannya terhadap ilmu pengetahuan spekulatif ini sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Sayangnya, meskipun secara intelektual sudah bisa dikatakan mapan, ia belum mendapatkan kepuasan yang diinginkan. Oleh sebab itulah, ia kemudian memutuskan untuk mengasingkan diri supaya bisa meneliti semua pengetahuan yang ia dapatkan secara jernih, bening, dan hening. Menelusuri setiap inci dari semua teori yang telah dipelajari guna menemukan titik lemah yang bisa diperbaiki. Menelisik Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 110 semua konsep yang ia ketahui untuk menemukan kekurangan yang bisa disempurnakan. Sebab, hanya dengan cara seperti ini ia bisa merekonstruksi semua konsep dan teori dalam sebuah susunan yang padu yang dapat mengobati ketidakpuasan intelektualitasnya. Metode mengasingkan diri untuk mencari solusi ini bukan suatu fenomena yang aneh atau baru dalam dunia Islam. Metode seperti ini bahkan memiliki landasan yang kuat dalam tradisi Islam karena pernah dipraktikkan Nabi Muhammad sebelum diutus menjadi nabi. Metode yang sama juga dilakukan oleh al-Ghazali sebelum menulis magnum opus-nya, Ihya' Ulumuddin. Jadi, mengasingkan diri ini merupakan suatu periode analisia dan penghayatan sebelum melakukan titik balik terhadap suatu realitas yang sudah dianggap mapan namun diyakini kurang memuaskan. Jadi, orang yang mengasingkan diri sejatinya adalah orang yang sudah memiliki bekal dan pengetahuan yang cukup tentang fenomena atau realitas yang menjadi zeitgest pada masa itu. Bukankah Nabi Muhammad melakukan uzlah ketika masyarakat Arab pra-Islam sudah merasa puas dengan kebudayaan mereka? Dan bukankah al-Ghazali juga ber-uzlah saat iklim intelektualitas Islam memiilki kecenderungan yang luar biasa terhadap kajian filsafat? Bertolak dari kenyataan ini, penulis berani memastikan bahwa tahapan memperoleh ilmu hudhuri yang diusulkan Suhrawardi bisa dilakukan hanya dan hanya jika seseorang sudah memiliki: [1] landasan kuat, [2] penguasan yang luas, [3] penghayatan yang mendalam atas disiplin ilmu pengetahuan yang digeluti. Tanpa ketiga faktor ini, praktis, semua tahapan Surawardian ini tidak bisa dioperasikan karena bukan hanya akan menghasilan kehampaan, tapi malah membuang-buang waktu dengan percuma. Tahap pertama ini mengantarkan pada tahap kedua yaitu, merasakan hadirnya cahaya Tuhan. Menurut Ziai, cahaya Tuhan ini mengambil bentuk serangkaian cahaya penyingkap (al-anwar al-sanihah) yang masuk ke dalam wujud manusia. Melalui cahaya-cahaya inilah seseorang memperoleh pengetahuan sejati yang ditandai dengan pengalaman-pengalaman tertentu yang bersifat personal. (Ziai, 1998, 36-37) Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 111 Pada tahap ini, seorang pencari kebenaran akan merasakan sebuah intuisi yang membuat semua persoalan berikut solusinya terlihat demikian nyata dan jernih. Cahaya-cahaya penyingkap tersebut menyinari dirinya lalu mencerahkan pengetahuannya sehingga ilmu pengetahuan yang diperoleh benar-benar pasti dan meyakinkan. Proses pencerahan seperti ini mengingatkan kita dengan konsep pencerahan yang dirasakan Sidarta Gautama setelah melakukan serangkaian proses pencarian kebenaran yang diakhiri dengan bersemedi di bawah pohon Bodhi. (Smith, 2001, 109-110) Tidak ada penjelasan empiris yang bisa dibuat untuk melukiskan proses kehadiran cahaya Tuhan ini ke dalam diri. Pengalaman ini mutlak bersifat personal-intuituf yang hanya bisa disampaikan secara singkat, dan tidak bisa dipaparkan secara subtil. Namun demikian, dari keterangan Suhrawardi dalam mukaddimah al-Masyari' wa al-Mutharahat, cahaya Tuhan (al-anwar al-ilahiyah) bisa disaksikan sedemikian rupa sehingga keberadaannya tidak bisa disangsikan. Tahap ketiga sekaligus yang terakhir adalah tahap merekonstruksi pengalaman personal tersebut dan berusaha menyusunnya secara sistematis sehingga bisa dibakukan sebagai suatu bentuk ilmu pengetahuan yang benar. Pada tahap ini, semua metoologi yang berlaku dalam ilmu pengetahuan ilmiah harus dioperasikan. Salah satunya adalah metode demonstrasi (posterior analytics) yang dalam terminologi Arab biasa disebut burhani. Suhrawardi meyakini bahwa metode yang dikemukakan Aristoteles ini cukup baik dalam menentukan validitas ilmu pengetahuan. Dalam Hikmah al-Isyraq secara tegas ia menulis: .ﻣﻘﺪﻣﺎت ﯾﻘﯿﻨﯿﺔ Bahwa pengetahuan sejati harus bisa diuji secara demonstratif, yaitu silogisme yang terstruktur dari premis-premis absolut (sangat positif dan meyakinkan). (Suhrawardi, 1993, 40) Terkait dengan ilmu hudhuri dalam sistem filsafat iluminasi ini, maka langkah dmonstratif yang dilakukan adalah menempatkan pengalaman personal yang dirasakan pada pengujian. Karena dalam pengalaman personal tersebut tidak ada data empiris yang bisa dijadikan sebagai instrumen pembuktian, tentu pembuktiannya juga tidak bersifat empiris seperti yang berlaku dalam disiplin Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 112 ilmu fisika, akan tetapi, sekali lagi, cukup dilakukan dengan uji konsistensi-logis postulat-postulatnya seperti yang diterapkan dalam disiplin matematika. Setelah ketiga tahap ini berhasil dilalui dengan sempurna, berarti takkan ada yang menghalangi seseorang untuk melangkah lebh jauh dengan menuliskan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan. Sebab, apabila ketiganya sudah berhasil dilalui, maka pengetahuan yang diperoleh sudah bisa dikatakan valid dan sangat siap untuk berkompetisi memperebutkan minat para pengkaji dan peneliti. Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 BAB 6 PENUTUP 6.1. Kesimpulan Dari paparan yang dimulai pada bab ke-1 hingga bab ke-5, setidaknya, ada tiga hal yang harus kita simpulkan secara singkat. Pertama, secara persona, Suhrawardi adalah filsuf jenius yang sulit dicarikan padanannya sejak masa sebelum ia hidup, sampai jauh sesudah ia wafat. Hal ini dibuktikan dengan kecemerlangannya dalam mengawinkan semua hikmah, kebijaksanaan, serta tradisi pemikiran filosofis yang berkembang dari masa ke masa di belahan dunia Barat dan Timur. Walaupun ketiga istilah ini—hikmah, kebijaksanaan, serta filsafat—secara holistik bisa dikatakan semakna, namun untuk kepentingan tertentu, penulis ingin membedakannya secara spesifik dengan memberikan titik acuan yang berbeda. Jika hikmah biasa dikaitan dengan ajaran agama dalam ranah teologi, maka kebijaksanaan lazim dihubungkan dengan mistisisme dalam ranah psikologi. Sedangkan filsafat seperti yang telah kita ketahui, sangat identik dengan seni olah pikir dan pendayagunaan nalar analitik. Kehebatan Suhrawardi dalam melebur ketiga spesies pilar pembangun peradaban umat manusia ini, bukan hanya membuat teori filsafatnya terdiri serta kental dengan aroma ketiganya, lebih dari itu, gagasannya memiliki sebutan unik yang, walaupun sudah tidak asing, tetap tidak kehilangan pesona yang membuncahkan rasa penasaran. Sebutan itu bernama teosofi. Terminologi yang berasal dari kata Yunani theosophia ini menurut Runnes, secara linguistik bisa diartikan dengan hikmah Tuhan, pengetahuan tentang ketuhanan. (Runnes, 1966, 317) Luar biasanya, Suhrawardi meraih prestasi ini dalam usia yang relatif hijau dibanding para pemikir sebelum dan sesudahnya yang, umumnya mencapai kematangan dalam berfilsafat di usia yang sudah senja. Sebagai seorang teosofos (ahli teosofi) yang oleh Nasr dimaknai sebagai orang yang mampu menyatukan antara latihan intelektual teoritis melalui filsafat dengan penyucian jiwa melalui sufisme, Suhrawardi menjelma jadi sosok elegan di mana kepribadiannya menjadi saksi atas adanya kekuatan batin yang besar, serta hati yang dipenuhi dengan cinta kepada Tuhan dan umat manusia. Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 114 Pengetahuan yang dimilikinya tidak hanya bercorak rasional, tapi juga yang termasuk dalam wilayah akal budi. Dia berhasil dengan gemilang menampilkan ciri khas filsuf Islam klasik yang biasa merangkap sebagai seorang ilmuwan yang bijaksana. Dialah sumber pengetahuan dan mata air cinta yang dalam dirinya terjalin antara filsafat dan spiritualitas dalam kesatuan yang memukau. Kedua, ditinjau dari segi pemikirannya, filsafat iluminasi tidak bisa dipungkiri telah berhasil menjadi bagian dari pelaku sejarah yang secara aktif dan dinamis memberikan solusi-solusi menarik terhadap pelbagai problem filosofis yang belum tuntas atau tidak bisa dijawab oleh aliran-aliran filsafat yang lain. Dalam sejumlah persoalan krusial, penjelasan-penjelasan filsafat iluminasi terbukti mampu memberikan jawaban yang lebih lengkap dibanding dengan teori filsafat lain, sehingga dengan demikian, kajian tentang filsafat ini tetap dan akan selalu aktual dari masa ke masa. Contoh kongkritnya adalah seperti yang penulis paparkan dalam bab 6, di mana dengan penalaran filosofis yang mendalam, ternyata kita bisa menemukan titik lemah yang rentan membuat konsep Cogito Deskartes tidak konsisten, atau bahkan salah kaprah. Ternyata, titik kelemahan itu sudah diantisipasi oleh filsafat iluminiasi dengan baik, sehingga konsep "Aku" menurut Suhrwardi jauh lebih mapan dibandingkan dengan yang refleksikan oleh Rene Deskartes. Ini belum termasuk banyaknya titik kelemahan yang ditemukan oleh Suhrawardi sendiri dalam aliran filsafat peripatetik yang sebagian ajarannya masih tetap dianut oleh banyak filsuf sampai sekarang. Ketiga, mengerucut pada konsep epistemologinya, kita dapati bahwa ilmu hudhuri merupakan konsep tentang ilmu pengetahuan yang noetic dan primordial. Noetic karena tindak mengetahui dalam ilmu hudhuri langsung terarah kepada realitas, kepada objek. Tindakan mengalami objek seperti ini memang berbeda dari pengetahuan metodis-ilmiah (scientific method) yang menyaratkan berkorelasinya subjek dan objek dan dibingkai dalam premis, "tidak ada subjek tanpa objek, dan tidak ada objek tanpa subjek." Akan tetapi, justru karena ciri khasnya yang noetic inilah ilmu hudhuri menjadi satu-satunya tipe epistemologi yang tidak hanya sanggup memetakan modus-modus pengetahuan dengan objek transitifnya yang terbentang luas di jagad raya, lebih dari itu, ia juga bisa Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 115 menguraikan pengalaman-pengalaman mistik spiritual dengan segala macam jenis objeknya yang imanen dan hanya bisa dirasakan dan tidak bisa diindra. Epistemologi ini dikatakan primoridal karena ilmu hudhuri bersifat primer, dasar, basis, implisit pada seluruh jenis pengetahuan manusia, dan mempunyai peran utama dalam bentuk dasar intelek manusia. Bahkan, ia merupakan konstituen utama makna pengetahuan itu sendiri. 6.2. Studi Kritis Atas Konsep Epistemologi Suhrawardi Jika pada bab pertama hingga bab kelima penulis terkesan berusaha sekuat tenaga untuk menjadikan teori ilmu hudhuri sebagai produk pemikiran epistemologi nomor wahid tanpa cacat dan tanpa cela, kini tibalah saatnya untuk bersikap lebih objektif dan menghindari subjektivisme berlebihan yang hanya akan membuat dinamika ilmu pengetahuan tak lagi progresif serta menghambat lahirnya konsep dan pemikiran baru yang lebih baik. Artinya, meskipun gagasan epistemologi Suhrawardi sudah baik, ia tetap saja merupakan hasil kreativitas manusia biasa yang pasti memiliki kekurangan. Tak ada istilah puncak dalam ranah ilmu pengetahuan apa pun, sehingga tak layak menasbihkan teori apa pun sebagai teori paripurna lalu membakukannya sebagai suatu teori yang sudah valid dan tak membutuhkan teori lagi tentang masalah itu di masa yang akan datang. Kita harus sadar bahwa pembakuan sama dengan pembekuan yang hanya akan melahirkan stagnasi dan kejumudan. Dunia Islam rasanya sudah sangat berpengalaman merasakan pahitnya stagnasi ilmu pengetahuan akibat ulah segelintir ilmuwan yang mengatakan bahwa pintu ijtihad sudah tertutup! Sikap objektif semacam ini harus kita kembangkan juga dalam melihat teori epistemologi iluminasi. Kita harus memandang teori tersebut sebagai teori yang belum final sehingga kesempatan untuk melahirkan teori epietemologi masih terbuka lebar bagi seluruh penggiat dan peminat kajian filsafat. Sebagai bukti bahwa teori itu belum sempurna, penulis akan coba memaparkan beberapa studi kritis yang bisa difungsikan sebagai koreksi sekaligus batu loncatan untuk menggagas konsep epistemologi yang lebih brilian. Pertama, apabila ditinjau dari segi semantik, akan tampak betapa Suhrawardi kurang piawai dalam menuangkan gagasan-gagasannya. Semua Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 116 paparan dalam Hikmah al-Isyraq—tidak hanya yang menyangkut masalah epistemologi—terbungkus dalam premis-premis pendek yang luar biasa rumit. Tidak ada alasan pasti mengapa Suhrawardi menggunakan gaya bahasa yang sulit dipahami seperti itu. Mungkin ia tidak ingin terjebak dalam narasi-narasi panjang yang berputar-putar dan melelahkan. Ia ingin supaya maksudnya lebih cepat disampaikan dan lebih cepat dipahami. Jika memang ini yang melandasi metodologi penulisannya, sudah sangat jelas bahwa hasratnya itu keliru. Bukannya mempercepat pemahaman para peneliti, struktur dan gaya bahasa semacam itu sebaliknya lebih sering menimbulkan kebingungan yang tak jarang malah membuat gagasannya tidak terpahami. Kondisi ini semakin akut saat kita membaca karya Suhrawardi secara keseluruhan, tidak hanya bagian tentang epistemologi. Obsesinya untuk menjadi seorang filsuf perenialis dengan melebur semua pemikiran yang berkembang di Barat dan di Timur, membuatnya tidak bisa menghindari penggunaan terminologiterminologi aneh yang sulit ditoleransi dari segi semantik. Suhrawardi seakan belum mengantisipasi perkembangan ilmu semantik masa kini yang menyaratkan agar penggunaan suatu kata harus mengacu kepada makna aplikatifnya yang konvensional. Untuk kasus ini penulis sedikit bisa memaklumi karena pada masa Suhrawardi, ilmu bahasa masih sangat sederhana. Kajian yang marak tentang bahasa pada saat itu juga hanya berkisar pada unsur gramatikal dan susastra. Belum ada kamus referensi resmi yang memuat pelbagai entri kata lengkap dengan registrasi maknanya yang sesuai. Di samping itu, penulis juga sadar bahwa dalam dunia filsafat, fenomena seorang pemikiran mengalami kebuntuan bahasa sehingga terpaksa menggunakan suatu istilah secara subjektif bukanlah perkara asing yang hanya terjadi pada Suhrawardi. Sampai saat ini pun, fenomena seperti itu tetap terjadi dan sering kita temui. Bagi mereka, kosakata yang sudah tersedia nampaknya belum cukup lengkap untuk bisa menguraikan penemuan mereka di bidang pemikiran spekulatif. Faktor ini jugalah yang mungkin bisa menjawab mengapa kita bertemu dengan kata différance saat mengkaji pemikiran Derrida, atau kata Leviathan saat membahas filsafat Hobbes. Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 117 Kedua, ada kesan inkonsistensi dan keraguan yang ditunjukkan Suhrawardi saat mengulas masalah definisi. Seperti dikupas dalam bab 4, sang iluminasionis begitu lincah saat menunjukkan kelemahan, mengkritisi, lalu mematahkan teori defiisi peripatetik. Ia bahkan tidak sungkan untuk menyatakan definsi sebagai metode yang mustahil melahirkan pengetahuan baru. Letak inkonsistensinya adalah, ia kemudian merumuskan sendiri teori definisi yang menurutnya lebih baik dan akurat dalam menjelaskan suatu objek. Kalau memang hanya ingin merumuskan suatu metode baru dalam membuat definisi, seberapa urgenkah menolak teori definisi yang sudah ada? Tidakkah ia cukup dengan menunjukkan kelemahan lalu mengajukan tawaran metode baru yang ia anggap lebih baik itu? Seandainya ia memang benar-benar sama sekali menolak definisi dengan segala macam bentuk pembuatannya, mungkin masih bisa dibenarkan posisi kritiknya. Akan tetapi pada faktanya ia hanya menutupi celah dan kekurangan metode pembuatan definisi yang ia tolak tersebut. Menurut hemat penulis, ini adalah ironi yang semestinya tidak perlu ia lakukan. Adapun keraguannya tercermin dari ketiadaan contoh yang ia sajikan berkenaan dengan metode pembuatan definisi yang ia tawarkan. Ini merupakan sesuatu yang di luar kebiasaan, mengingat Suhrawardi lazimnya memberikan contoh nyata dalam setiap teori yang ia paparkan. Ketika menjelaskan tentang dua jenis pengetahuan manusia misalnya. Ia bisa dengan merinci—secara definitif— salah satu modus pengetahuan tersebut, sehingga walaupun tidak merinci modus yang lain, pembaca secara otomatis bisa memahaminya. Anehnya, ia tidak melakukan hal yang sama saat mengulas teori definisi. Tidak ada alasan yang jelas mengapa ia bersikap demikian. Akibatnya, penulis hanya bisa mengandaikan dua hal. Pertama, karena memang definisi yang ia gagas itu mustahil untuk diwujudkan. Kedua, karena ia berusaha untuk bersikap konsisten dengan penolakannya terhadap definisi, sehingga bahkan untuk jenis definisi yang ia tawarkan sendiri pun, ia enggan untuk membuatkan contohnya. Kalau pengandaian pertama yang benar, maka semua klaim terhadap teori definsi Suhrawardi—seperti yang dilakukan Razavi dengan menyebutnya sebagai konbinasi dari teori definisi Platonian dan Aristotelian—dengan sendirinya menjadi runtuh. Lebih ekstrem lagi, kita boleh Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 118 saja mengatakan bahwa Suhrawardi sejatinya tidak menawarkan metode apa pun dalam pembentukan definisi. Namun jika pengandaian kedua yang benar, konsekuensinya kita bisa menyalahkan Suhrawardi sendiri, dan menasihatinya bahwa tidak selamanya konsistensi intelektual itu harus dicirikan dengan penafian untuk memberikan contoh terhadap suatu teori yang sebagiannya ditolak tapi sebagiannya lagi diterima. Tekad untuk bersikap konsisten yang ingin ditunjukkan Suhrawardi dalam kasus ini adalah tekad yang salah tempat dan tak bisa dibenarkan. 6.3. Posisi Epistemologi Suhrawardi Adalah suatu fenomena yang sulit didustakan bahwa para peneliti yang bergumul dengan ilmu pengetahuan dewasa ini sangat akrab dengan dua jenis epistemologi—yaitu epistemologi observatif dan epistemologi demonstratif— serta mengabaikan jenis epistemologi yang ketiga yaitu epistemologi iluminatif. Satu di antara sekian banyak faktor yang melatari fenomena ini mungkin adalah karena kedua jenis epistemologi yang tersebut pertama lebih aktif mewarnai perkembangan ilmu pengetahuan dari masa ke masa sejak dilahirkan dari haribaan tradisi pemikiran Yunani klasik, tepatnya oleh dua pemikir besar yang namanya sering dikutip dalam kajian filsafat; yakni Plato dan Aristoteles. Konsekuensi logis dari perlakuan yang kurang adil terhadap jenis epistemologi yang ketiga ini adalah, banyak kalangan yang bukan hanya merasa sekadar asing, alih-alih malah bersikap antipati dan menganggapnya mustahil diterapkan dalam ilmu pengetahuan yang konsisten dan rigorus. Mereka masih belum bisa melepaskan diri dari asumsi yang menyatakan ilmu hudhuri dan epistemologi iluminasinya sebagai epistemologi yang hanya bisa diterapkan pada ranah spiritualitas-mistik dan tidak lebih. Asumsi seperti ini menggejala secara merata, tidak hanya di kalangan cendekiawan Barat saja, tapi juga di kalangan Muslim sendiri. Pada titik ini, siapa pun pasti sulit menentukan posisi yang tepat bagi epistemologi iluminasi dan ilmu hudhuri. Serangkaian pertanyaan pun menyeruak ke permukaan dan harus segera mendapatkan jawaban, seperti "Bisakah kita memberikan posisi yang setara bagi epistemologi iluminasi seperti yang kita Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 119 berikan pada dua jenis epistemologi lainnya?" atau, "Bisakah kita memosisikan epistemologi jenis ini sebagai salah satu sarana untuk menemukan solusi bagi pelbagai problem ilmu pengetahuan yang sampai saat ini masih belum final?" atau yang lebih ekstrem lagi, "Bisakah metode analisa yang ditawarkan epistemologi iluminasi disajikan lalu dipertanggungjawabkan secara ilmiah?" Dalam kondisi seperti ini, langkah yang paling urgen menurut hemat penulis, bukan menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, akan tetapi mencari akar masalah yang menyebabkan pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Hal ini menjadi penting karena seperti yang dipaparkan dalam bab-bab kajian ini, terbukti dengan jelas betapa epistemologi iluminasi memiliki energi yang cukup untuk mengikuti kompetisi sportif di medan ilmu pengetahuan. Ia juga memiliki daya untuk memberikan solusi komprehensif bagi persoalan ilmu pengetahuan, dan analisaanalisa yang ditawarkannya juga valid sera bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, bagi orang yang memahami ilmu hudhuri, pertanyaan-pertanyaan bernada negatif seperti di atas takkan pernah terajukan. Atas dasar itulah, penulis berani mengasumsikan bahwa penilaian parsial seperti di atas lebih disebabkan karena kurang mendalamnya pengetahuan mereka terhadap epistemologi iluminasi, bukan karena kurangnya kapabilitas yang dimiliki spesies epistemologi ini untuk mendapatkan posisi bergengsi seperti yang dinikmati oleh kedua spesies epistemologi lainnya. Jelasnya, pandangan miring tersebut dikarenakan para cendekiawan belum memiliki pengetahuan yang utuh tentang ilmu hudhuri, dan bukan karena ilmu hudhuri tidak bisa memecahkan pelbagai problem yang kerap terjadi di bidang epistemologi. Penulis sadar secara prima facie bahwa asumsi tanpa indikasi ibarat justivikasi tanpa bukti. Tidak bisa dibenarkan dengan alasan apa pun dan tidak boleh dilakukan oleh siapa pun. Oleh sebab itulah, penulis akan menghadirkan indikasi yang secara jelas bisa mengukuhkan kebenaran asumsi tentang ketidakutuhan pengetahuan sebagian kalangan terhadap ilmu hudhuri. Indikasi itu bisa kita lihat dalam disertasi tentang Suhrawardi yang ditulis oleh Amroeni Drajat yang berhasil ia pertahankan di depan dewan penguji UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dalam kesimpulannya terhadap kritik epistemologi Suhrawardi terhadap epistemologi peripetetik, Drajat menulis: Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 120 Ilmu hudhuri merupakan tawaran yang dikemukakan Suhrawardi berkenaan dengan problem epistemologi. Meskipun demikian, tidak semua pengetahuan harus diperoleh melalui jenis ilmu ini, sebab pada sisi lain Suhrawardi juga mengakui fungsi-fungsi pancaindra, baik lahir (luar) maupun batin (dalam). Ilmu hudhuri nampaknya memiliki lapangan operasional sendiri yang bersifat spiritual, universal, dan bertumpu pada aspek pengalaman batin yang bersifat rasa. (Drajat, 2005, 165) Dari penyimpulan yang mempersulit ilmu hudhuri untuk memperoleh posisi strategis ini, ada beberapa—tidak hanya satu—hal yang bisa kita pertanyakan dan kita koreksi. Mari kita mulai koreksi ini dari aspek yang paling sederhana, yaitu dengan menemukan kesalahan persepsional terhadap instrumen pengetahuan yang ia sebut "pancaindra". Dalam kutipan di atas, Drajat menulis "Suhrawardi juga mengakui fungsi-fungsi pancaindra, baik lahir (luar) maupun batin (dalam)." Seandainya ia tidak melakukan kesalahan tulis, maka kesalahan yang paling kentara dalam kalimat tersebut adalah penggunaan dimensi batin terhadap kata "pancaindra". Sebab, dalam terminologi keseharian yang sudah jamak di kalangan masyarakat, kata "pancaindra" selalu mengacu kepada lima indra ekstrinsik yang dimiliki manusia yang meliputi, mata (indra penglihatan), hidung (indra penciuman), telinga (indra pendengaran), lidah (indra perasa), kulit (indra peraba). Dengan kata lain, tidak pernah ada acuan intrinsik apa pun bagi pancaindra, karena indra yang bersifat intrinsik kalaupun memang ada, biasa disebut indra keenam, dan itu pun tidak jelas apa yang diacu, apakah itu akal, hati, atau yang lainnya. Kalimat yang jelas salah ini kemudian ia turunkan sebagai konsekuensi dari rangkaian kalimat sebelumnya yang berbunyi, "Meskipun demikian, tidak semua pengetahuan harus diperoleh melalui jenis ilmu ini " Penilaian ini dengan mudah dapat memberikan dua asumsi atau dua kesan lain yang bisa dipertanyakan. Pertama, ilmu hudhuri baginya terkesan sebagai ilmu yang sangat terbatas dan tidak bisa menjawab persoalan-persoalan epistemologis secara tuntas. Modus ilmu hudhuri hanya bisa dioperasionalkan pada medan tertentu dan untuk menghasilkan pengetahuan yang tertentu pula. Tidak bisa dioperasionalkan secara holistik dalam seluruh aspek tindak mengetahui. Asumsi ini diperkuat dengan serangkaian kalimat yang ada di akhir kutipan di atas, di mana secara tegas ia Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 121 menyatakan bahwa ilmu hudhuri hanya bisa dioperasionalkan pada lapangan yang bersifat spiritual. Pembatasan medan operasional ilmu hudhuri pada ranah spiritualitas belaka seolah menyiratkan bahwa bagi Drajat, ilmu hudhuri dirancang oleh Suhrawardi hanya untuk mengilmiahkan data-data visioner yang bersifat spiritual dan intuitif saja, dan tidak bersentuhan dengan data-data indrawi yang bersifat faktual dan empiris. Padahal pada bab 2 penulis sudah menjelaskan bagaimana cara ilmu hudhuri beroperasi dengan data-data indrawi. Apakah hanya karena Suhrawardi menolak kategori definisi Aristotelian dan merumuskan teori penyaksian (musyahadah) untuk mengetahui sesuatu, kemudian kita boleh menyimpulkan bahwa ilmu hudhuri mutlak melangit dan tidak membumi? Tidak, sama sekali tidak. Drajat nampaknya tidak sadar dengan risiko yang harus ia tanggung akibat penilaian seperti itu. Bukankah jika rumusan teori ilmu hudhuri hanya bersifat intuitif, dia bisa menilai bahwa Suhrawardi berarti masih menyisakan persoalan dalam bidang epistemologi? Bila statemen ini disetujui, konsekuensi logisnya dia juga harus menilai upaya keras Suhrawardi untuk melakukan rekonstruksi terhadap epistemologi mengalami kegagalan? Konsekuensi lebih lanjutnya adalah, Drajat juga harus berpendapat bahwa teori epistemologi Suhrawardi bukanlah hasil dari sintesa integral dari dua aliran kebijaksanaan—aliran diskursif dan aliran intuitif—yang berbeda. Konsekuensi terakhir, ia harus mencabut pertanyataannya bahwa sistem filsafat Suhrawardi dihasilkan dari kehebatan Suhrawardi dalam menggabungkan seni olah pikir (rasio) dan olah rasa (intuisi) sebagai intrumen dalam mencari kebenaran. Mengapa? Karena ia harus mengakui bahwa epistemologi sebagai salah satu aspek kajian dari filsafat itu, ternyata tidak dihasilkan dari penggabungan kedua instrumen yang biasa dilakukan untuk mencari kebenaran itu sendiri. Padahal sepanjang pembacaan terhadap tulisan Drajat, penulis tidak menemukan satu kalimat pun yang mengindikasikan penolakan Drajat terhadap pengakuan Suhrawardi yang menasbihkan dirinya sebagai penyintesa pelbagai kebijaksanaan klasik dalam satu wadah yang bernama filsafat iluminasi. Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 122 Penulis yakin, Drajat tidak sadar dengan rentetan konsekuensi yang harus ia tanggung akibat tulisan singkatnya itu. Suatu konsekuensi yang lucunya, berbentuk gradatif di mana konsekuensi yang satu menghasilkan konsekuensi berikutnya secara berkesinambungan, persis seperti bentuk gradasi iluminasi cahaya yang ia jadikan sebagai tema kajian tesis magisternya. Sebab, jika ia menyadari konsekuensi dari statemennya itu, ia pasti takkan menulis kesimpulan akhir seperti di atas. Berdasarkan kenyataan ini, maka asumsi penulis yang awalnya mungkin hanya bisa ditempatkan pada tataran hipotesa, sekarang sudah bisa dijadikan sebagai tesa. Yaitu bahwa, bagi orang-orang yang tidak memahami secara utuh dan menyeluruh, posisi ilmu hudhuri dalam sistem epistemologi iluminasi tetap akan berada di bawah bayang-bayang kedua jenis epistemologi lain yang memang lebih akrab dan lebih sering dipergunakan oleh masyarakat. Akan tetapi, bagi orang yang mengetahuinya secara utuh, maka ilmu hudhuri yang digagas oleh Suhrawardi akan menempati posisi teratas yang lebih unggul dari kedua jenis epistemologi lainnya. Namun demikian, penulis takkan menghalangi orang yang ingin bersikap objektif dan realistik dengan memosisikan epistemolgi hudhuri ini setara dan sejajar dengan kedua "saudaranya", dengan catatan orang itu terlebih dahulu harus mengetahui jenis epistemologi ini secara mendalam. 6.4. Rekomendasi untuk Kajian Lebih Lanjut Sebelum mengakhiri kajian ini, penulis ingin menyampaikan bahwa, meskipun ada kepuasan tersendiri yang hadir dan memenuhi seluruh relung kalbu setelah berhasil menuntaskan penulisan karya ini, penulis tetap merasa ada yang kurang dan belum bisa memaparkan konsep ilmu huduri secara lengkap dan tuntas. Hal itu terjadi bukan karena minimnya waktu yang dimiliki, namun lebih disebabkan minimnya wawasan serta terbatasnya pemahaman penulis terhadap pemikiran Suhrawardi. Atas dasar itulah, walaupun secara pribadi penulis merasa bahagia bisa menyajikan salah satu teori dalam filsafat iluminasi ini ke tengah-tengah komunitas pencinta refeleksi filosoofis tanah air, penulis merasa karya ini belum sempurna sehingga setiap koreksi, kritik, serta saran pasti penulis terima dengan Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 123 gembira dan senang hati. Namun demikian, rasanya tidak muluk jika penulis berharap karya ini dijadikan sebagai sumber inspirasi atau setidaknya batu pijakan untuk melakukan studi yang lebih mendalam terhadap teori ilmu hudhuri, atau bahkan terhadap konsep filsafat iluminasi secara holistik dan konprehensif. Berkaca dari pengalaman pribadi yang mungkin layak untuk dipertimbangkan, bagi siapa pun yang berhasrat untuk menelusuri labirin pemikiran filsuf muda nan jenius, Suhrawardi, sekurang-kurangnya ada empat hal yang ingin penulis rekomendasikan. Pertama, penguasaan bahasa Arab yang memadai. Hal ini penting karena Suhrawardi menulis karyanya hanya dalam dua bahasa. Yaitu Arab dan Persia. Bahasa Arab lebih urgen untuk dikuasai mengingat sebagian besar karya Suhrawardi dituangkan ke dalam bahasa ini. Memang, saat ini hampir atau mungkin sudah semua karya filsuf muda ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis, Inggris, dan Indonesia. Akan tetapi, rasanya sangat sulit untuk mendapatkan hasil yang memuaskan jika kita mengandalkan hasil terjemahan tersebut untuk meneliti pemikiran filsafat iluminasi. Sebagai misal, dalam pasal yang berisi ulasan tentang pembagian ilmu pengetahuan, dalam Hikmah al-Isyraq yang disunting Henry Corbin serta komentatornya Quthbuddin al-Syirazi, ada bagian yang berjudul fi Muqassim al-Tashawwur wa al-Tashdiq (Pembagian Pengetahuan ke dalam Konsepsi dan Konfirmasi). Menurut Hossein Ziai, istilah konsepsi dan konfirmasi sebenarnya bukanlah istilah-istilah iluminasi dan tidak digunakan oleh Suhrawardi dalam Hikmah al-Isyraq. Bahkan, kata Tashdiq hanya digunakan sekali dalam Hikmah al-Isyraq, itu pun memiliki arti "afirmasi", bukan "konsepsi". Al-Syirazi dan Corbinlah yang menerjemahkan Tashdiq dengan "konfirmasi" sebagai usaha mereka untuk memodifikasi pandangan-pandangan Suhrawardi supaya sesuai dengan skema peripatetik tradisional. (Ziai, 1998, 134) Di satu sisi, terobosan yang dilakukan al-Syirazi dan Corbin ini dapat memudahkan para peneliti yang ingin mengkaji konsep epistemologi iluminasi. Namun di sisi lain, tidak menutup kemungkinan malah menjebak para peneliti tersebut pada kesimpulan keliru dengan menyakatakan bahwa Suhrawardi membagi pengetahuan manusia ke dalam dua jenis—yaitu konsepsi dan Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 124 konfirmasi—yang sama persis dengan pembagian yang dilakukan kaum peripatetik. Atas dasar itulah, Ziai dengan lantang menolak terobosan ini dan mengingatkan kita bahwa kedua istilah tersebut tidak berasal dari Suhrawardi. Namun ini menjadi sebuah penandaan yang tidak benar tepat atas bagian ini dan harus ditolak. Al-Syahrazuri, yang menulis Syarh Hikmah Isyraq lebih meyakinkan untuk tujuan-tujuan iluminasionis Suhrawardi daripada al-Syirazi, mengihindari istilah-istilah konsepsi dan konfirmasi. (Ziai, 1990, 134) Selain "konsepsi" dan "konfirmasi", tidak menutup kemungkinan masih ada terminologi lain yang sejatinya tidak pernah ditulis oleh Suhrawardi, namun ditambahkan oleh para komentatornya dengan tujuan-tujuan tertentu seperti di atas. Atau boleh jadi ada suatu terminologi yang, karena kepentingan, tujuan atau faktor tertentu, tidak diterjemahkan sebagaimana mestinya. Kemungkinankemungkinan semacam ini selalu terbuka jika yang dijadikan rujukan bukanlah karya asli yang ditulis oleh Suhrawardi. Berangkat dari kenyataan ini, praktis, penelitian dalam filsafat iluminasi berikut segenap lingkup kajiannya, bisa dikatakan absah dan valid jika dan hanya jika peneliti yang bersangkutan menguasai bahasa yang digunakan oleh sang pemikir untuk mewartakan gagasan-gagasannya. Jika tidak, maka tingkat akurasi hasil penelitian itu sangat mungkin untuk dipertanyakan. Kedua, diperlukan kesabaran yang tinggi untuk memahami karya Suhrawardi, khususnya Hikmah al-Isyraq. Mengapa? Karena bahasa dalam karya itu bukan hanya singkat dan berbelit-belit, tapi juga dipenuhi beragam istilah yang tidak mengacu pada makna konevensional seperti yang kita kenal. Apabila tidak hati-hati, kita akan dengan mudah terjerumus ke dalam pemahaman yang salah. Untuk kasus kalimat singkat dan berbelit, penulis sudah banyak mengetengahkan contoh kutipan langsung dalam karya ini. Sedangkan untuk kasus istilah yang tidak mengacu kepada makna konvensionalnya, di samping istilah malaikat seperti yang sudah penulis paparkan pada bab 2, contoh lainnya adalah kata barzakh. Dalam pemahaman kaum Muslimin, makna kata ini mengacu pada alam kubur, suatu periode kehidupan yang harus dijalani setelah mati dan sebelum pengadilan akhirat. Tapi dalam Hikmah al-Isyraq, kata itu Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 125 bermakna objek-objek pertengahan antara gelap dan terang—seperti penulis singgung dalam bab 5. Untuk memahami istilah-istilah seperti ini, mutlak diperlukan kesabaran dan ketelitian yang tinggi selama proses pembacaan karya Suhrawardi. Berkaitan dengan masalah ini, penulis merasa beruntung karena dalam pasal-pasal yang mengulas masalah epistemologi, Suhrawardi sama sekali tidak mencantumkan istilah-istilah ciptaannya sendiri itu. Ketiga, pemilihan tema secara spesifik. Dalam hal ini kita harus sadar bahwa sekarang kita hidup di zaman yang serba detil dan terperinci, sehingga disipilin ilmu pengetahuan pun semakin mengerucut kepada bagian-bagian yang subtil. Sebagai misal, jika dulu kita hanya mengenal disiplin biologi sebagai ilmu hayat yang membahas tentang hewan dan tumbuhan secara general, sekarang disiplin itu sudah semakin spesifik yang meliputi zoologi, botani, bakteriologi, dan lain sebagainya. Dengan semangat yang sama dan untuk menghasilkan penelitian yang lebih terperinci, ada baiknya jika dalam membahasa teori epistemologi iluminasi, fokus kajian kita hanya berkisar pada salah satu aspeknya saja, seperti aspek dimensi empirisnya, atau dimensi intuitifnya, atau bahkan pada tahapan cara memperoleh ilmu hudhuri saja. Metode seperti ini memang takkan menghasilkan kunatitas halaman yang tebal, namun penulis yakin, kualitas hasil penelitian seperti ini pasti jauh lebih mendalam dan lebih memuaskan. Keempat, mengikuti saran Suhrawardi dalam membaca karya-karyanya. Inilah satu di antara sekian banyak keistimewaan Suhrawardi sekaligus yang membedakannya dari filsuf lain di semua zaman. Dengan jelas ia menyarankan agar siapa pun yang berminat mengkaji filsafat iluminasi, hendaknya membaca karya-karyanya secara berurutan karena menurutnya, ia menulis semua karyanya secara sistematik dan berkesinambungan. Tegasnya, jika ingin meneliti teori filsafat iluminasi, akan lebih baik jika kita memulai kajian dari karya pertama yang memang diproyeksikan sebagai pendahuluan, berlanjut kepada karya berikutnya yang memang sengaja diproyeksikan sebagai karya lanjutan, dan demikianlah seterusnya hingga berakhir pada master pies-nya. Menurut Suhrawardi, urutan pembacaan terhadap karyanya harus dimulai dari al-Talwihat, kemudian berlanjut kepada al-Muqawamat, diteruskan kepada Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 126 al-Masyari' wa al-Mutharahat, dan diakhiri pada Hikmah al-Isyraq. Pembacaan yang teratur seperti ini akan menghasilkan kesan yang utuh tentang pemikiran Suhrawardi, betapa pun keempat karya itu memiliki corak dan metode penulisan yang berbeda-beda. Karya pertama al-Talwihat misalnya, ditulis sesuai dengan metodologi filsafat peripatetik, sedangkan Hikmah al-Isyraq ditulis berdasarkan metode iluminasionis. Tapi karena Suhrawardi sudah merancang metodologi pembacaan terhadap karya-karyanya itu, kita kemudian tidak bisa menyimpulkan bahwa al-Talwihat adalah periode di mana Suhrawardi menganut pemikiran peripatetik, sedangkan Hikmah al-Isyraq adalah periode di mana ia sudah beralih menjadi iluminasionis. Periodisasi seperti ini mutlak tidak bisa diberlakukan kepada Suhrawardi, walaupun boleh diberlakukan kepada para filsuf lain yang hidup sebelum atau sesudahnya. Contohnya kepada Ludwig Wittgenstein seperti yang dilakukan oleh Bertens. Berdasarkan perubahan kecenderungan pemikiran filsuf bahasa tersebut, Bertens dengan mudah memetakan dua peride filosofis dalam kehidupan Wittgenstein. [1] peride Tractatus Logico-philoshopicus yang ditandai dengan analisis bahasa melalui picture theori. Ia menegaskan klaim bahwa bahasa hanya bermakna bila mengacu kepada dunia eksternal, dunia faktual, dan proposisi tautologis-matematis. Sebuah pandangan yang mengukuhkan pandangan atomisme logis. [2] Periode Philosophical Investigations yang ditandai dengan ketertatarikannya kepada bahasa biasa yang menurutnya jauh lebih kaya dan beragam dari bahasa logika. Menurutnya, bahasa digunakan dengan beragam cara dan tujuan yang masing-masing memiliki aturan tertentu seperti halnya aneka ragam permainan yang beroperasi dalam aturan-aturan yang telah disepakati. Pandangannya ini kemudian populer dengan istilah Language Games (permainan bahasa). (Bertens, 2002, 44-54) Anjuran Suhrawardi tentang urutan pembacaan terhadap karyanya menunjukkan bahwa pemikirannya tidak mengalami perubahan yang bisa dipetakan dalam periodisasi. Dengan kata lain, gagasan filsafat iluminasi sudah utuh dalam benaknya sebelum ia menulis karya-karyanya yang mengesankan metamorfosa pemikiran filsafat dari yang bernuansa peripatetis-empiris hingga yang bercorak iluminasionis-intuitif. Anjuran tersebut, tertuang dalam masing- Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 127 masing karyanya yang berjudul al-Talwihat, al-Muqawamat, dan al-Masyari' wa al-Mutharahat. Dalam akhir al-Talwihat ia menulis: ... .ﻟﺘﯿﺼﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻤﺎء Daam buku ini saya sudah memaparkan pandangan yang memungkinkan seseorang tak lagi membutuhkan yang lain (maksudnya adalah metode peripatetik) dalam seni ini... Berhentilah mengulas "ilmu yang dipelajari" saja, dan beralihlah kepada "ilmu yang dialami dan disaksikan" supaya Anda menjadi seorang filsuf. (Suhrawardi, 1993, 120-121) Kemudian dalam pengantar al-Muqawamat, ia menyatakan bahwa karya tersebut ditulis sebagai penjelas bagi karya sebelumnya yang berjudul alTalwihat, dan oleh karena itu, ia menulisnya sesuai dengan metode yang ia gunakan dalam menulis karya yang pertama tadi. (Suhrawardi, 1993, 124) Sedangkan mengenai karya ketiga yang berjudul al-Masyari' wa alMutharahat, secara tegas Suhrawardi menyarankan agar karya ini dibaca sebelum mengkaji Hikmah al-Isyraq, tapi sesudah mengkaji dua karya sebelumnya yaitu al-Talwihat dan al-Muqawamat. Dalam mukaddimahnya ia menulis: .ﺑﺎﻟﺘﻠﻮﯾﺤﺎت Buku ini (al-Masyari' wa al-Muthawarat) harus dikaji sebelum membacanya (Hikmah al-Isyraq), tapi setelah membaca karya ringkas yang berjudul al-Talwihat. (Suhrawardi, 1993, 194) Mengikuti saran sang filsuf dalam membaca karya-karyanya bukan hanya akan memudahkan pemahaman seorang peneliti terhadap konsep filsafat iluminasi secara komprehensif, lebih dari itu, dapat meminimalisir kesalahpamahaman yang mungkin terjadi karena faktor-faktor teknis dan non-teknis seperti dijelaskan di atas. Jadi, selamat membaca! Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 DAFTAR PUSTAKA Abdullah, Amin, (1999), Studi Agama: Normativitas atau Historisitas? cet. Ke-2, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Abdullah, Taufik (t.t) Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, cet. Ke-1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. Ad-Dimyathi, Abu Bakar, (t.t.) Inayah al-Thalibin, cet. Ke-1, Beirut: Dar al-Fikir Affifi, A. E., (1995), Filsafat Mistis Ibn Arabi. cet. Ke-2. Jakarta: Gaya Media Pratama. al-Ghazali, (t.t.) Maqasid al-Falasifah, cet. Ke-1, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah _____, (t.t.), Mi‘yar al-‘Ilm (edit: Sulayman Dunya), cet. Ke-1, Mesir: Dar alMa‘arif. _____, (2001), Sumber Segala Cahaya (terj. Muhammad Baqir), Jakarta: Hikmah. _____, (1966), Tahafut al-Falasifah (edit: Sulayman Dunya), cet. Ke-4, Mesir: Dar al-Ma‘rifah. al-Sadr, Muhammad Baqir, (1989), Falsafatuna, cet. Ke-15, Lebanon: Dar al-Ta‘aruf li al-Mathbu‘at. Al-Sinqithi, Ahmad Walad al-Kuri al-'Alawi, (t.t.) Bulughu Ghayah al-Amani fi alRatbi 'Ala Miftah al-Tijani, cet. I, Maktabah Syamilah. al-Taftazani, Abu al-Wafa' al-Ghanimi, (1985) Sufi dari Zaman ke Zaman (terj. Ahmad Rofi' Utsmani), cet. Ke-1, Bandung: Pustaka. al-Rifa'i, Ahmad bin Ali bin Tsabit, (1408) Burhan al-Mu'ayyad, cet. Ke-1, Beirut: Dar al-Kitab al-Nafis. Bagus, Lorens, (2002), Kamus Filsafat, cet. Ke-3, Jakarta: Gramedia. Bakhtiar, Amsal, (1999), Filsafat Islam, cet. Ke-3, Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Bertens, Kess, (2006), Filsafat Barat Kontemporer Prancis, cet. Ke-4, Jakarta: Gramedia. _____, (2002), Filsafat Barat Kontemporer Inggris-Jerman, cet. Ke-4, Jakarta: Gramedia. Chittick, William C., (2001), Tuhan-tuhan Sejati dan tuhan-tuhan Palsu (terj. Ahmad Nidjam), cet. Ke-1, Yogyakarta: Qalam. Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 129 De Boer, T.J., (1954), Tarikh al-Falsafah fi al-Islam (terj. Muhammad ‘Abd al-Hadi Abu Zaydah), cet. Ke-1, Beirut: Dar al-Nahdhah al-‘Arabiyyah. Drajat, Amroeni, (2001), Filsafat Iluminasi, cet. Ke-1, Jakarta: Riora Cipta, _____, Suhrawardi: (2005), Kritik Falsafah Peripatetik, cet. Ke-1, Yogyakarta: LkiS. Dunya, Sulaiman, (t.t.), al-Haqiqah fi al-Nazhr al-Ghazali, cet. Ke-1, Kairo: Dar alMa‘arif, Eliade, Mircea (ed), (t.t.), The Encyclopedia of Religion, New York: Macmillan Publishing Company. Fakhry, Majid, (1986), Sejarah Filsafat Islam (terj. Drs Mulyadhi Kartanegara), cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Jaya, _____, (2001), Sejarah Filsafat Islam: Sebuah Peta Kronologis (ter. Zaimul Am), cet. Ke-1, Bandung: Mizan. _____, (1988), al-Masysya'yah al-Qadimah, cet. Ke-I, Ma'had al-Inma' al-Arabi. Froe, A. de., dkk, (1988), Berpikir Secara Kefilsafatan (terj. Soejono Soemargono), cet. Ke-1, Yogyakarta: Nur Cahaya. Ghalib, Musthafa, (1979), Ibn Sina, cet. Ke-1, Beirut: Maktabah al-Hilal. Ghazi, Muhammad Jamil, al-Shufiyyah wa al-Wajh al-Akhar, dalam www.saaid.net. Hadiwijono, Harun, (1999), Sari Sejarah Filsafat Barat, cet. Ke-1, Yogyakarta: Kanisius, Hanafi, Ahmad, (1996), Pengantar Filsafat Islam, cet. Ke-6, Jakarta: Bulan Bintang. Hatta, Mohammad, (1980), Alam Pikiran Yunani, Cet. Ke-1, Jakarta: Tirtamas. Hidayat, Komaruddin, (1996), Memahami Bahasa Agama; Hermeunetik, cet. Ke-1, Jakarta: Paramadina, Sebuah Kajian Iqbal, Mohammad, (1992), Metafisika Persia (Terj. Joebar Ayoeb), cet. Ke-3, Bandung: Mizan. Jisr, Nadim, (1963), Qishshah al-Iman, cet. Ke-1, Beirut: Dar al-Andalus. Kaelan, (2005), Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Filsafat, cet. I, Yogyakarta: Kartanegara, Mulyadhi, (2002), Menembus Batas Waktu, cet. Ke-1, Bandung: Mizan. _____, (2003), Menyibak Tirai Kejahilan, cet. Ke-1, Bandung: Mizan. Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 130 Kattsoof, Louis O., (1986), Pengantar Filsafat (terj. Soejono Soemargono), cet. Ke-1, Yogyakarta: Tiara Wacana. Lubis, Akhyar Yusuf, (2004) Masih Adakah Tempat Berpijak Bagi Ilmuwan, cet-Ke1, Bogor: Akademi. _____, (2004), Filsafat Ilmu: Metodologi Posmodernis, cet-Ke-1, Bogor: Akademi. Mahmud, ‘Abd al-Qadir, (t.t.), al-Falsafah al-Shufiyyah fi al-Islam, cet. Ke-1,.Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi. Manshur, Layli, (2002), Ajaran dan Teladan Para Sufi, cet. Ke-1, Jakarta: Srigunting. Ma'luf, Louis, (1997), al-Munjid fi al-Lughghah wa al-A'lam, cet. Ke-24, Beirut: Dar al-Masyriq. Nasr, Seyyed Hossein, (ed), (2003), Ensiklopedi Tematis Filsafat Islam, (terj. Tim Penerjemah Mizan), cet. Ke-1, Bandung: Mizan. _____, (1986), Sains dan Peradaban di Dalam Islam (terj. Mahyudin), cet. Ke-1, Bandung: Penerbit Pustaka _____, (1978), Shadruddin al-Syirazi & Trancendence Theosophy, Teheran: Imperial Iranian Academi of Philosophy. _____, (1969), Three Muslim Sages, Cambrigde: cet. Ke-2, Harvard University Press. _____, (1987), Tradisional Islam in the Modern Word, London & New York: Kegan Paul Internasional. Nasution, Harun, (1999), Filsafat dan Mistisisme dalam Islam, cet. Ke-10, Jakarta: Bulan Bintang. Netton, Ian Richard, (1994), Allah Trancendent, cet. Ke-1, England: Curzon Press Limited. Runes, Dagobert De, (1971), Dictionary of Philosophy, cet. Ke-1, New Jersey: Littlefield Adam & Co. Russell, Bentrand, (2004), Sejarah Filsafat Barat (terj. Sigit Jatmiko), cet.. Ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Rusyd, Ibnu, (2004), Tahafut al-Tahafut, (terj. Khalifurrahman Fath), cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Schimmel, Annemarie, (1986), Dimensi Mistik dalam Islam (terj. Achdiati Ikram), cet. Ke-1, Jakarta, Pustaka Firdaus. Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009 131 Sholeh, A. Khudori, (2004), Wacana Baru Filsafat Islam, cet. Ke-1,Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Siregar, H.A. Rivay, (1999), Tasawuf Dari Sufisme Klasik ke Neo-Sufisme, cet. Ke-1, Jakarta: Rajawali Press. Smith, Huston, (2001), Agama-agama Manusia (terj. Saafruddin Bahar), Cet. Ke- , Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Sudarminta, J, (1991), Filsafat Proses: sebuah Pengantar Sistematik Filsafat Alfred North Whitehead, cet. Ke-1, Yogyakarta: Kanisius. Suhrawardi, (2003), Hayakil al-Nur (terj. Zaimul Am), cet. Ke-1, Jakarta: Serambi. _____, (1993), Majmu‘ah Mushannafat Syaykh al-Isyraq I, cet. Ke-1, Teheran: Institut d’Etudes et des Recherches Culture. _____, (1993) Majmu‘ah Mushannafat Syaykh al-Isyraq II, cet. Ke-1, Teheran: Institut d’Etudes et des Recherches Culture. Strathern, Paul, (2001), 90 Menit Bersama Deskartes (terj. Frans Kowa), cet. Ke-1, Jakarta: Erlangga. Syaraf, Muhammad Jalal Abu al-Futuh, (1975), Allah wa al-‘Alam wa al-Insan fi alFikr al-Islami, cet. Ke-1, Mesir: Dar al-Ma‘arif. Syarif, MM., (ed), (1993), Para Filosof Muslim (terj. Ilyas Hasan), cet. Ke-5, Bandung: Mizan. Yazdi, Mehdi Ha’ri, (2003), Epistemologi Iluminasionis (Terj. Ahsin Muhammad), cet. Ke-1, Bandung: Mizan. Zar, Sirajuddin, (2004), Filsafat Islam: Filosof dan Filsafatnya, cet. Ke-1, Jakarta: Rajawali Press. Ziai, Hossein, (1998), Suhrawardi dan Filsafat Iluminasi, (terj. Afif Muhammad), cet. Ke-1, Bandung: Zaman Wacana Ilmu. Universitas Indonesia Ilmu Hudhuri..., Luqman Junaidi, FIB UI, 2009