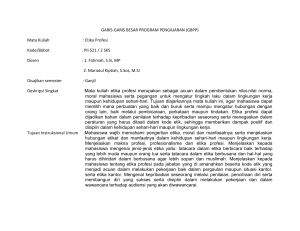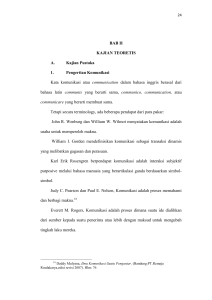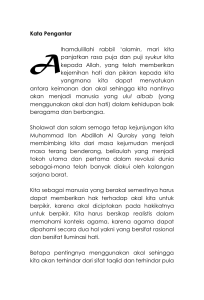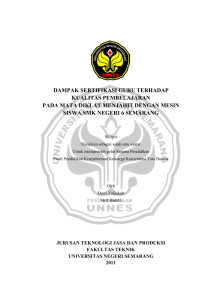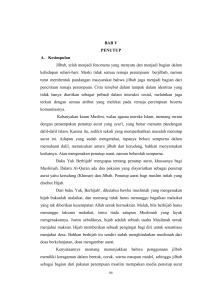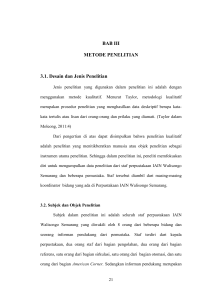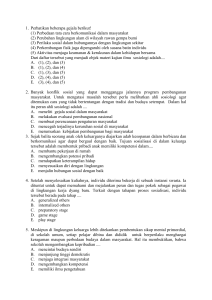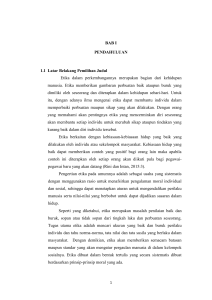etika berbusana - EJOURNAL | Universitas Narotama Surabaya
advertisement

ETIKA BERBUSANA (Studi Kasus Terhadap Pola Berbusana Mahasiswi IAIN Walisongo Semarang) TESIS Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Magister Dalam Ilmu Agama Islam Oleh: HATIM BADU PAKUNA NIM 5202020 PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2005 HALAMAN PENGESAHAN 2 DEKLARASI Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa tesis ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga tesis ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan. Semarang, 2 Juni 2005 Deklarator HATIM BADU PAKUNA NIM 5202020 3 ABSTRAKSI Etika Islam merupakan aturan baik dan buruk perbuatan manusia yang disandarkan pada ajaran-ajaran Islam. Etika Islam mencakup cara bergaul, duduk, berjalan, makan-minum, tidur, dan pola berbusana. Artinya, ada patokan-patokan yang harus diikuti. Seperti dalam pola berbusana, menurut Ibrahim Muhammad Al-Jamal dalam bukunya, Fiqh Wanita, mengatakan; seorang muslimah dalam berbusana hendaknya memperhatikan patokan; menutupi seluruh tubuh selain yang bukan aurat yaitu wajah dan kedua telapak tangan, tidak ketat, tidak tipis menerawang, tidak menyerupai pakaian lelaki, dan tidak berwarna menyolok. Namun patokan-patokan pola berbusana muslimah tersebut sampai saat ini masih menjadi perdebatan, utamanya jilbab. Apakah ia mencirikan kesalehan, sebagai penutup aurat rambut dan leher, atau hanya sebatas identitas wanita muslimah. Di satu sisi, jilbab menjadi simbol pakaian muslimah santri, terutama yang berasal dari pesantren. Di sisi lain, ia dijadikan busana yang lazim dikenakan hanya pada momen-momen kerohanian; shalat, pengajian, berkabung, bahkan saat menghadiri pesta pernikahan; sebaliknya tidak dipakai pada berbagai aktivitas kesehariannya. Kalangan selebritis sibuk menutupi kepalanya yang biasa terbuka itu dengan jilbab di bulan Ramadhan. Jelas pemakaian jilbab tak ada hubungan dengan kesalehan maupun ketaatan beragama. Sebab, begitu bulan suci itu usai, jilbabnya pun dilepas. Bagi mereka, berjilbab hanyalah tuntutan pasar; strategi untuk meraup keuntungan material dengan penampakan spiritual dan eksploitasi agama. Begitu pula mahasiswi IAIN Walisongo Semarang yang notabene memakai jilbab sebagai salah satu simbol identitas perguruan tinggi yang berbasis ilmu-ilmu keislaman. Setelah dilakukan penelitian terhadap mahasiswi yang tergabung dengan KAMMI, HMI, IMM, PMII, UKM Music, Teater dan Mawapala, ternyata banyak keragaman pola berbusana yang mereka dipakai, seberagaman corak pemahaman keagamaan mereka. Mahasiswi yang bergabung dengan KAMMI memahami bahwa pola busana yang dipakai oleh seorang muslimah (termasuk mahasiswi) seharusnya yang longgar sehingga dapat menutup aurat rapat-rapat, tidak boleh transparan/ketat, sebab dengan pola berbusana seperti itu diharapkan membawa pemakainya pada perilaku yang mencerminkan etika Islam. Mahasiswa yang bergabung dengan HMI, IMM dan PMII memahami bahwa pola berbusana muslimah yang penting dapat menutup aurat, bentuknya tidak harus longgar, yang penting masih kelihatan sopan. Sebaliknya, mahasiswi yang bergabung dengan UKM Music, Teater dan Mawapala, lebih memahami bahwa busana yang seharusnya dipakai mahasiswi harus mengikuti mode, sehingga mengesankan mahasiswi IAIN tidak ketinggalan zaman dalam berbusana. Merekapun merefleksikan pemahamannya tentang pola berbusana dengan berbusana yang mereka pakai. Selanjutnya, manakah pemahaman keagamaan dan pola berbusana mahasiswi IAIN yang sesuai dengan etika Islam, inilah yang dikaji dalam tesis ini. 4 KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, berkat ketekunan dan usaha maksimal penulis, penyusunan tesis yang berjudul “ETIKA BERBUSANA (Studi Kasus Terhadap Pola Berbusana Mahasiswi IAIN Walisongo Semarang)” dapat terselesaikan. Penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada: 1. Prof. Dr. Abdul Djamil, M.A., selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang. 2. Prof. Dr. Abdurrahman Mas’ud, M.A., selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Walisongo. 3. Dr. Abdul Muhayya, M.A., selaku dosen pembimbing yang banyak memberikan arahan dan koreksi hingga terselesaikannya tesis ini. 4. Dr. Ahmad Gunaryo, M.Soc.Sc. dan Drs. Darori Amin, M.A., selaku Asisten Direktur I dan Asisten Direktur II Program Pascarjana IAIN Walisongo. 5. Segenap dosen Pascasarjana IAIN Walisongo yang telah memberikan bekal pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan jejang studi S-2. 6. Segenap pegawai administrasi dan karyawan Pascasarjana yang telah banyak memberikan layanan akademik selama study di Pascasarjana. 7. Segenap pegawai Perpustakaan IAIN, Perpustakaan Pascasarjana, dan Perpustakaan Fakultas Ushuluddin yang telah memberikan layanan dalam peminjaman buku-buku referensi. 5 8. Segenap keluarga penulis yang banyak memberikan dorongan baik materiil maupun moriil dalam menempuh studi. 9. Teman-teman penulis yang ikut memberikan dorongan dan membantu dalam menyelesaikan tesis ini, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satupersatu. Semoga Allah S.W.T. membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna baik dari aspek materi, metodologi dan analisisnya. Karenanya, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk karya yang lebih baik di masa mendatang. Akhirnya hanya kepada Allah S.W.T. penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya. Semarang, 2 Juni 2005 Penulis, HATIM BADU PAKUNA NIM 5202020 6 PEDOMAN TRANSLITERASI Transliterasi Arab-Latin ا a ض dl ب b ط th ت t ظ zh ث ts ع ‘ ج j غ gh ح h ف f خ kh ق q د d ك k ذ dz ل l ر r م m ز z ن n س s و w ش sy ﻩ h ص sh ء ’ ي y 7 Untuk Mâd dan Diftong â = a panjang î = i panjang û = u panjang او = aw او = uw اي = ay اي = iy Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah atau qamariyah, yakni ‘al’ ditulis sama. Contoh: اﻟﻘﺮان = al-Qur’ân اﻟﺴﻴﺪة = al-Sayidah اﻟﻌﻮام = al-‘Awâm = اﻟﺸﺮﻳﻌﺔal-Syarî’ah 8 DAFTAR SINGKATAN S.W.T. S.a.w. R.a. H.R. H. M. Q.S. NU PMII HMI IMM KAMMI MAWAPALA UKM PKS Ibid. Op.cit. Loc.cit. Hlm. T.th. Dkk. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Suhanahu Wa Ta’ala Shalalllahu ‘alaihi wasalam Radiyalllahu anhu Hadits Riwayat Hijriyah Masehi Al-Qur’ân Surat Nahdlatul Ulama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Himpunan Mahasiswa Islam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Mahasiswa Walisongo Pecinta Alam Unit Kegiatan Mahasiswa Partai Keadilan Sejahtera Ibidem (pada tempat yang sama) Opere cicato (dalam karangan yang telah disebut) Loco cicato (pada tempat yang telah dikutip) Halaman Tanpa tahun Dan kawan-kawan 9 MOTTO DAN PERSEMBAHAN Motto: “Siapa yang memakai pakaian (yang bertujuan mengundang) popularitas, maka Allah akan mengenakan untuknya pakaian kehinaan pada hari kemudian, lalu dikobarkan pada pakaiannya itu api”. (H.R. Abu Daud). Tesis Ini Penulis Persembahkan Kepada: - Mama “Monira Datau” dan Papa “Badu Pakuna” - Kakak-kakaku tersayang; “Kak Wahid, Kak Amran, Tata Rama, Aci Hasna dan Daci Wati”. - Teman-temanku terkasih terutama “Mamang” thanks for everything 10 DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL ................................................................................. i HALAMAN NOTA PEMBIMBING ........................................................ ii HALAMAN PENGESAHAN ................................................................... iii HALAMAN DEKLARASI ....................................................................... iv HALAMAN ABSTRAKSI ........................................................................ v HALAMAN KATA PENGANTAR .......................................................... vi HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ........................................... viii HALAMAN DAFTAR SINGKATAN ........................................................ x HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ........................................ xi HALAMAN DAFTAR ISI ......................................................................... xii BAB I BAB II PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah .................................................. 1 B. Rumusan Masalah ............................................................ 10 C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian ................................. 10 D. Tinjauan Pustaka ............................................................. 11 E. Metode Penelitian ........................................................... 15 F. Sistematika Penulisan ..................................................... 18 DISKURSUS-DISKURSUS ETIKA A. Istilah Etika ...................................................................... 20 B. Norma Dasar Etika .......................................................... 24 C. Etika Islam dan Norma-normanya ................................... 27 D. Etika Berbusana .............................................................. 34 E. Etika Berbusana; Tinjauan Fungsi .................................. 38 F. Kontroversi Jilbab ........................................................... 54 11 BAB III ETIKA BERBUSANA MAHASISWI IAIN WALISONGO SEMARANG A. Dinamika dan Ragam Corak Pemikiran Keagamaan Mahasiswa IAIN Walisongo ................................................... 61 B. Pemahaman Keagamaan dan Pola Berbusana Mahasiswi IAIN Walisongo ....................................................................... C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pola Berbusana Mahasiswi IAIN Walisongo .................................................... BAB IV ANALISIS TERHADAP ETIKA 73 79 BERBUSANA MAHASISWI IAIN WALISONGO SEMARANG A. Analisis Terhadap Pemahaman Mahasiswi IAIN Walisongo tentang Pola Berbusana dan Implikasinya ..... 84 B. Analisis terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pola Berbusana Mahasiswi IAIN Walisongo .......................... 100 C. Pola Ideal Etika Berbusana Mahasiswi IAIN Walisongo . 108 BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ..................................................................... 113 B. Saran-saran ...................................................................... 116 C. Kata Penutup ................................................................... 117 DAFTAR PUSTAKA 12 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Etika merupakan problem asasi yang dihadapi setiap manusia baik secara inidividu maupun kolektif. Batasan etika sendiri menurut para pakar, termasuk pakar pendidikan sulit dicari parameternya, sehingga memunculkan ragam perspektif. Perpedaan persepsi inilah yang semestinya dipandang sebagai aset yang perlu dihargai dan didiskusikan. Jika suatu etika telah tertanam, maka problem selanjutnya yaitu pemeliharaannya yang jauh lebih sulit dibanding mengumpulkan informasinya. Sebab erat kaitannya dengan suasana batin (naluri batin manusia). Naluri manusia sendiri masih menjadi sumber vital bagi setiap aktivitas hidup. Idealnya naluri bisa ditundukkan di bawah kendali akal. Jika sampai menyimpang dari kendali akal, dapat menghalangi cara pandang manusia. Kemudian membatasi pengaruhnya supaya orang yang tidak berpikir dipaksa untuk mengikuti kecenderungan-kecenderungan yang bertentangan dengan logikanya. Di sinilah disadari peran penting menyelaraskan komponen naluri dan akal sehingga diperoleh pola kehidupan yang beretika yang didasari prinsip-prinsip moral.1 Praktek prinsip-prinsip moral atau etika akan melibatkan sejumlah kesulitan dan tidak jarang melahirkan kontradiksi. Oleh karena itu, 1 Lihat Sayid Mujtaba Musawi Lari, Ethics and Spiritual Growth, terj. M. Hasyim Assagaf ”Etika dan Pertumbuhan Spiritual”, Jakarta: Lentera Basritama, 2001, hlm. xi. 13 pendidikan dan pelatihan yang tidak berbasis spiritualitas tidak dapat menolak naluri yang melemahkan. Orang yang tidak mempunyai pengamanan spiritualitas akan segera terpengaruh oleh hawa nafsu. Karena, pendidikan semacam itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan dominasi hawa nafsu. Akibatnya, etikanya pun menyimpang dari prinsip-prinsip moral. Oleh karena itu, keyakinan religius merupakan jaminan yang cukup penting bagi pelaksanaan prinsip-prinsip manusiawi dan sebagai dukungan yang paling besar bagi nilai-nilai etika dalam melawan hawa nafsu. Manusia dapat membebaskan dirinya dari cengkraman dorongan-dorongan dan motifmotif yang merugikan melalui keimanan kepada Sang Pencipta, adanya hari balasan, pahala dan dosa. Tujuan para Nabi, terutama Nabi Muhammad s.a.w. ialah mendidik etika manusia untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih tinggi, dan membersihkan pikiran mereka dari pencemaran dan kotoran. Penyebaran etika Islam, yang dilancarkan oleh Nabi merupakan gerakan unik, tanpa tandingan, dari sisi pandang etos tentang kedalaman dan keasliannya yang konstruktif. Etika Islam menjadi unik dalam pengertian bahwa ia meliputi semua kehalusan rohani manusia dan perhatian khusus kepada setiap gerak pikiran dan yang berasal dari batin. Dampak yang belum pernah ada sebelumnya yang dilakukan pada jiwa manusia dan realitas dari kehidupan ialah mengangkat suatu umat yang rusak menuju ketinggian martabat.2 2 Ketika masyarakat yang bobrok itu diberi keimanan dan bimbingan, ia meletakkan fondasi dari tatanan baru di dunia dan maju sehingga ia menjadi suatu model moralitas dan keutamaan manusia, suatu model yang sepertinya belum pernah dilihat sejarah. Bahkan sekarang, ketika kekosongan ruhani menandai watak dan ruh Barat abad ke-20, ketika orang-orang yang dibesarkan 14 Abad modern3, yang ditandai dengan perkembangan berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, juga bisa meninggalkan problem serius. Sekadar contoh, dengan semakin majunya teknologi informasi, orang bukan saja dapat menikmati beberapa stasiun televisi di dalam negeri, tetapi juga bisa menikmati siaran lain dari luar negeri. Apa yang diperbuat dan dilakukan oleh bangsa-bangsa yang berbudaya dan berperadaban lain, bisa ditonton. Mereka yang silau oleh kemajuan peradaban bangsa lain, berusaha menirunya tanpa selektif. Dengan peniruan yang tidak mempertimbangkan apakah hal itu sesuai dengan normanorma agama serta adat istiadat yang berlaku di tempatnya dan apa pula akibatnya bagi dirinya dan generasi sesudahnya, akhirnya patokan-patokan moral yang tadinya diagungkan mulai memudar. Nilai-nilai lama yang sakral, dengan sendirinya terkikis oleh nilai-nilai baru. Kalau dahulu kaum wanita merasa malu karena terlihat betis kakinya, sekarang justru sebagian dari mereka bangga untuk mempertontonkan semua bagian tubuhnya kepada siapa saja. Pembicaraan tentang seks, yang dahulu merupakan suatu hal yang tabu, sekarang menjadi pembicaraan di mana saja dengan tidak rasa pekewuh sedikitpun. Bahkan dengan alasan untuk seni, orang tidak malu mempertunjukkan gerakan apa dalam lingkungannya datang berlindung di tangan Islam, terjadi suatu perubahan total dalam rohani dan etosnya. Para ilmuwan Amerika telah mengakui bahwa ketika orang-orang AmerikaAfrika masuk Islam, semua aspek kehidupan mereka mengalami perubahan mendalam. Lihat Muhammad Yusuf Musa, Filsafat al-Akhlak fi al-Islam, Cairo: Maktabah al-Khanji, 1963, hlm. 45 3 Biasa disebut era globalisasi. Disebut demikian, karena perkembangan informasi maju dengan sedemikian pesatnya, sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi di belahan dunia, bisa diikuti dan disaksikan di tempat lain pada waktu yang sama. Dunia seakan menjadi semakin sempit tanpa batas-batas teritorial. 15 saja, termasuk gerakan yang paling pribadi kepada khalayak umum.4 Kasus goyang “ngebor” yang dipertontonkan Inul Daratista beberapa waktu yang lalu sebagai salah satu contohnya. Di samping masih banyak lagi contoh yang lebih seronok, yang menunjukkan betapa patokan-patokan etika telah mengalami pergeseran. Yang jelas, budaya malu, yang menjadi benteng pertahanan manusia dari perbuatan-perbuatan amoral, sekarang telah runtuh. Otoritas moral yang berupa adat kebiasaan, kode moral, pernyataan tentang suatu kaidah, lembaga-lembaga keagamaan, karya sastra yang disakralkan, hukum alam, kekuasaan negara yang dianggap mempunyai pengaruh dalam menegakkan moral, sekarang sudah ditinggalkan dan dianggapnya sebagai masa lalu. Anggapannya, suatu kemajuan hanya bisa dicapai dengan cara memberontak terhadap nilai-nilai yang sudah mapan. Sesudah tidak ada lagi kepercayaan terhadap otoritas moral yang sudah mapan, timbulah relatifisme yang memandang benar atau salah itu berbeda-beda menurut tempat dan waktu. Suatu hal yang dianggap benar, pada suatu tempat dan waktu, belum tentu benar menurut tempat yang sama, tetapi waktunya berlainan. Apalagi pada tempat dan waktu yang berbeda. Benar dan salah adalah relatif. Ada pula yang memandang bahwa moral itu subyektif, juga relatif. Moral itu berubah dan berkembang sesuai dengan situasi yang ada. Para penganjur etika ini menghormati kaidah-kaidah etika dan kebijaksanaan yang telah ada. Tetapi, kaidah dan kebijaksanaan itu dianggap sebagai pedoman 4 Lihat M. Darori Amin, “Norma-norma Etika Islam”, dalam Teologia, Volume 12, Nomor 3, Oktober, 2001, hlm. 319. 16 yang dapat dikesampingkan jika situasinya demikian. Joseph Fletcher mengatakan bahwa segala tindakan atau perbuatan apa saja adalah benar atau salah tergantung kepada situasi yang ada.5 Perbedaan sandaran moralitas ini membuahkan persepsi etika yang berbeda-beda. Pada akhirnya, perbuatan baik dan buruk, patokannya berbeda-beda, tergantung dari perspektif mana ia dipandang. Islam sendiri telah memberikan sandaran etika. Bahkan, etika islam dipandang bisa memberikan kepastian dan kemantapan dalam menentukan baik buruknya suatu perbuatan, karena bersumber dari wahyu yang mutlak dan obyektif. Meski mutlak dan obyektif, etika Islam itu juga mengakui adanya kemubahan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan situasi, sepanjang tidak bertentangan dengan wahyu itu sendiri. Salah satu kaidah dalam ushul fiqh mengatakan bahwa hukum berjalan sesuai dengan illat yang menyertainya.6 Bagi umat Islam, permasalahan etika tidak dapat dipisahkan dari keyakinan kaum muslimin terhadap eksistensi Tuhan Yang Maha Esa, mutlak dan transenden, serta syari’ahnya yang kokoh, sebagaimana hal itu juga terdapat pada agama lain.7 Tuhan, menurut keyakinan mereka tidak hanya 5 Lihat Harold H. Titus, dkk., Persoalan-persoalan Filsafat, Jakarta: Bulan Bintang, 1984, hlm. 141-162. 6 Lihat misalnya Wahbah al-Zuhaily, Ushul al-Fiqh al-Islami, Jilid I, Beirut: Dâr al-Fikr, 1986, hlm. 755. 7 Pada dasarnya, fitrah manusia sebagai mahluk yang memiliki hati nurani, adalah religius. Seorang bayi mungil akan diam sejenak ketika mendengar suara adzan dari masjid maupun televisi, karena gelombang getaran suara adzan menyambung dengan getaran hati nurani sang bayi. Hati nurani adalah 'danau religiusitas' tempat suara-suara religiusitas bersemayam, dan sering hanya dapat didengar kalau seseorang bisa merenung dalam sepi dan sendiri. Karena itulah, Nabi perlu menyepi di Gua Hira, melepaskan diri dari kegalauan peradaban jahiliyah, untuk dapat 17 sebagai pencipta (al-Khaliq) tetapi juga sebagai pembimbing atau petunjuk bagi perjalanan sejarah dan pengatur segala bentuk keteraturan alam semesta. Atau Tuhan juga sebagai al-Mudabbir (pengatur) dan al-Rabb (pembimbing, pendidik) bagi seluruh alam. Teori etika merupakan gambaran rasional mengenai hakikat dan dasar perbuatan dan keputusan yang benar serta prinsip-prinsip yang menentukan klaim bahwa perbuatan dan keputusan tersebut secara moral diperintahkan atau dilarang. Oleh karena itu bahasan etika selalu menempatkan tekanan khusus terhadap definisi konsep-konsep etika, justifikasi atau penilaian terhadap keputusan moral, sekaligus membedakan antara perbuatan atau keputusan yang baik dan buruk. Sistem etika harus berkaitan secara memadai dengan aspek-aspek moral yang bermakna dan koheren.8 mendengarkan suara hati nuraninya dan menerima kabar kebenaran sejati. Umat lain pun melakukan metode serupa untuk mendengar bisikan nurani dan menerima bersitan cahaya Tuhan. Lihat Ahmadun Yosi Herfanda, “Membongkar Ruang Sempit Sastra Religius” dalam Http://www.republika.co.id. Tgl. 1 Agustus, 2004. 8 Al-Qur'an melibatkan pembahasan seluruh kehidupan moral, keagamaan dan sosial muslim, tidak berisi teori-teori etika dalam arti yang baku sekalipun ia membentuk keseluruhan ethos Islam. Jadi bagaimana cara mengeluarkan ethos ini menjadi sangat penting dalam studi etika Islam. Ada tiga hal yang menjanjikan arah di mana penelitian tentang etika dapat membuahkan hasil, yang kesemuanya itu kembali kepada teks al-Qur'an itu sendiri; tafsir, fiqh dan kalam. Para sufi dan filosof, yang sering menggali otoritas al-Qur'an untuk mendukung pernyataan teoritis dan etika mereka tidak dapat dikatakan telah membangun pandangan Islam yang menyeluruh mengenai alam dan manusia. Mereka telah berhutang budi kepada pengaruh-pengaruh luar seperti India, Yunani, Kristen dan lainnya telah membentuk pemikiran mereka. Oleh karena itu, teoriteori etika mereka ditandai dengan kompleksitas yang tinggi yang menyusunnya sebagian berasal dari teori-teori umum yang berakar dari al-Qur'an dan sunnah. Teori-teori tersebut mungkin dibentuk sebagai teori skriptual atau teologis yang bergantung kepada keluasan mereka bertumpu kepada teks kitab suci atau kesepakatan terhadap teks yang dapat diterima ketika menghadapi nilai atau intepretasi secara dialektik. Lihat Majid Fakhry, Ethical Theories in Islam, terj. Zakiyuddin Baidhawi “Etika dalam Islam”, Jakarta: Pustak Pelajar, 1996, hlm. xv-xvi. 18 Selanjutnya etika menjadi suatu ilmu yang normatif,9 dengan sendirinya berisi norma dan nilai-nilai yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Titik berat penilaian etika ialah perbuatan baik atau jahat, susila atau tidak susila. Manusia dalam semua perbuatannya, bagaimanapun juga mengejar sesuatu yang baik. Berbuat baik merupakan tanggung jawab moral bagi semua manusia, dan pelaksanaan dari tanggung jawab ini sebagai pencerminan dari jiwa yang berpribadi. Bertanggung jawab berarti pula memfungsionalkan sifat-sifat manusia untuk mempertahankan nilai-nilai pribadi yang luhur, serta dapat mendudukkan nilai harga diri manusia sebagai manusia. Kemudian manusia selalu memikirkan prinsipprinsip tentang masalah mana yang benar dan mana yang salah. Persoalannya, ukuran norma baik-buruk berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, sebagaimana dalam pandangan relatifisme di atas. Suatu hal yang baik dan benar di suatu tempat, mungkin akan dianggap salah atau jahat di tempat yang lain. Pola hubungan dan perbuatan apapun sangat diperhatikan oleh Islam. Karena Islam memperhatikan etika, dikenalah apa yang disebut “etika Islami” seperti cara bergaul, duduk, berjalan, makan-minum, tidur, pola berbusana, dll. Artinya, ada patokan-patokan yang harus diikuti. Seperti dalam pola berbusana, menurut Ibrahim Muhammad Al-Jamal dalam 9 Karena dikatakan sebagai ilmu, maka penjelasan makna baik, buruk, hak dan kewajiban moral tidak dapat dipisahkan dari proses aktivitas rasional (akal manusia). Artinya, etika bukanlah sebagai ajaran/doktrin yang harus diikuti begitu saja (taklid buta) oleh manusia, tetapi ia merupakan “metode” atau “filsafat moral” untuk memahami benar atau salahnya suatu doktrin/ajaran moral itu sendiri. Lihat Burhanuddin Salam, Etika Individual; Pola dasar Filsafat Moral, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm. 3. 19 bukunya, Fiqh Wanita, mengatakan; seorang muslimah dalam berbusana hendaknya memperhatikan patokan; menutupi seluruh tubuh selain yang bukan aurat yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Tidak ketat sehingga masih menampakkan bentuk tubuh yang ditutupinya. Tidak tipis menerawang sehingga warna kulit masih bisa terlihat. Tidak menyerupai pakaian lelaki Tidak berwarna menyolok sehingga menarik perhatian orang.10 Patokan-patokan pola berbusana muslimah tersebut sampai saat ini masih menjadi perdebatan, utamanya jilbab. Apakah ia mencirikan kesalehan atau hanya sebatas identitas wanita muslimah. Jika jilbab dianggap sebagai pola busana muslimah, maka perlu ditelusuri lebih dalam. Jilbab sendiri masih sarat makna. Jilbab tidak hanya dipakai oleh orang tua, tapi juga para remaja, pekerja di kantor, instansi maupun pemerintahan, para artis, bahkan para pelacur sekalipun. Di satu sisi, jilbab menjadi simbol pakaian muslimah santri, terutama yang berasal dari pesantren. Di sisi lain, ia dijadikan busana yang lazim dikenakan hanya pada momen-momen kerohanian; shalat, pengajian, berkabung, bahkan saat menghadiri pesta pernikahan; sebaliknya tidak dipakai pada berbagai aktivitas kesehariannya. Jilbab lebih dari sekadar kewajiban, tapi simbol kultural yang membedakan komunitas mereka (santri) dengan komunitas lainnya (abangan dan non-muslim). Kalangan selebritis sibuk menutupi kepalanya yang biasa terbuka itu dengan jilbab di bulan Ramadhan. Jelas pemakaian jilbab tak ada hubungan dengan kesalehan maupun ketaatan beragama. Sebab, begitu bulan suci itu usai, jilbabnya pun 10 Ibrahim Muhammad Al-Jamal, Fiqh Wanita,Bandung: Gema Insani Press, 2002, hlm. 130 20 dilepas. Bagi mereka, berjilbab hanyalah tuntutan pasar; strategi untuk meraup keuntungan material dengan penampakan spiritual. Begitu pula para pelacur di Nangroe Aceh Darusalam (NAD) misalnya. Mereka menyembunyikan identitasnya dengan memakai jilbab.11 Mengingat posisinya sebagai pekerja seks dalam ruang sosial dianggap hina, kotor, dan melecehkan moralitas, mereka harus mencari simbol sebagai alibi stereotip itu. Dengan memakai jilbab, mereka ingin eksistensi dan identitas mereka diakui dan dihormati di tengah-tengah masyarakat. Jadi, tidaklah layak jika menggeneralisir bahwa perempuan berjilbab itu berarti suci, sopan, dan saleh. Begitu pula sebalikya, perempuan tidak berjilbab dicitrakan sebagai perempuan kotor, kurang sopan, dan tidak taat beragama. Proporsi di atas menjadi menarik jika dikaitkan dengan pola berbusana mahasiswi IAIN Walisongo, yang memiliki simbol identitas tersendiri seakan menunjukkan sebagai perguruan tinggi yang berbasis ilmu-ilmu keislaman dan difokuskan mengakaji ilmu-ilmu keislaman pula. Kemudian apakah pola berbusana demikian, utamanya memakai jilbab bagi mahasiswi IAIN Walisongo hanya sebatas simbol kultural yang membedakan dengan perguruan tinggi umum, atau memang sebagai etika religius berbusana yang dijunjung tinggi? Jika benar, lalu bagaimana femonema banyaknya busana yang dipakai mahasiswi IAIN yang masih kelihatan seronok, misalnya walaupun memakai jilbab, tapi dipadukan dengan baju, celana yang super ketat, tansparan, sehingga kelihatan lekuk-lekuk tubuhnya. Hal inilah yang menarik untuk dilakukan penelitian. 11 Lihat Sri Rahayu Arman, “Jilbab; Antara Kesucian dan Resistensi”, dalam Http://www.islamlib.com. Tgl. 19 Januari 2003. 21 B. Rumuan Masalah Berdasarkan deskripsi di atas maka permasalahan yang akan diteliti dan dicari jawabannya adalah: 1. Bagaimanakah pemahaman mahasiswi IAIN Walisongo dalam hal etika berbusana? 2. Bagaimanakah implikasi dari pemahaman etika berbusana mahasiswi IAIN Walisongo tersebut? 3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pola berbusana mahasiswi IAIN Walisongo? C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian Berdasarkan pokok permasalahan yang diangkat pula, maka penelitian ini mempunyai tujuan: 1. Untuk mendeskripsikan pemahaman mahasiswi IAIN Walisongo dalam hal etika berbusana. 2. Untuk mengevaluasi implikasi dari pemahaman etika berbusana mahasiswi IAIN Walisongo. 3. Untuk mengungkap faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pola berbusana mahasiswi IAIN Walisongo. Setelah dikemukakannya tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini mempunyai signifikansi yang jelas dan dapat dijadikan rujukan. Minimal dijadikan bahan diskusi bagi civitas akademika IAIN Walisongo pada khususnya dan praktisi pendidikan keagamaan pada umumnya, agar dapat 22 membimbing, mengarahkan dan memberikan stressing tertentu terhadap mahasiswi, agar etika religius berbusana terarah pada kondisi yang diharapkan. D. Tinjauan Pustaka Kajian tentang masalah etika banyak ditemukan dalam buku-buku maupun dalam bentuk penelitian-penelitian lapangan. Selanjutnya untuk membahas persoalan-persoalan di atas, berikut penulis ilustrasikan beberapa buku yang dipandang terkait. Fadwa El Guindi dalam bukunya yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia; Jilbab; Antara Kesalehan, Kesopanan dan Penawaran mengemukakan bahwa berjilbab lebih merupakan identitas serta kerahasiaan pribadi dari sisi ruang dan tubuh. Wacana publik tentang jilbab seringkali berputar-putar pada pertanyaan: apakah ia sebuah ekspresi kultural Arab ataukah substansi ajaran agama; apakah ia sebuah simbol kesalehan dan ketaatan seseorang terhadap otoritas agama ataukah simbol perlawanan dan pengukuhan identitas memandangnya seseorang? sebagai sebuah Banyak bias feminis kultur “beraliran” patriarkhi serta Barat tanda keterbelakangan, subordinasi dan penindasan terhadap perempuan. Pada titik ini, jilbab sebenarnya masuk pada arena kontestasi—sebuah permainan makna dan tafsir. Relasi-kuasa bermain dan saling tarik antara kalangan agamawan normatif dan feminis liberal; antara atas nama kepentingan norma (tabu, aurat, kesucian, dan privasi) dan atas nama kebebasan perempuan 23 (ruang gerak, persamaan dll). Dalam konteks kekinian, jilbab juga menjadi simbol identitas, status, kelas dan kekuasaan. Menurut Crawley, misalnya, pakaian adalah ekspresi yang paling khas dalam bentuk material dari berbagai tingkatan kehidupan sosial sehingga jilbab menjadi sebuah eksistensi sosial, dan individu dalam komunitasnya.12 Majid Fakhry dalam bukunya Etika dalam Islam, melakukan kajian yang intens mengenai akhlak, dengan melakukan teoritisasi etika dalam Islam. Sehingga norma-norma akhlak Islam yang diformulasikan dalam teoriteori itu, kemudian dapat dijabarkan dalam langkah-langkah nyata yang lebih konstektual serta menyentuh persoalan umat, namun tetap di atas prinsipprinsip Islam, yang bersumber pada al-Qur'an dan sunnah. Fakhry rupanya banyak menggunakan metode horizontal dalam kajiannya yang semata-mata mengikuti garis perkembangan kronologis, dan metode analitis atau skematis yang berkaitan dengan tema-tema besar etika yang vertikal. Tipologi resultan teori-teori besar etika di dalam kerangka definisi yang jelas, di mana tipe skriptual dan tipe filosofis adalah dua hal yang bertentangan. Selanjutnya, buku ini mengemukakan tentang moralitas skriptual, etika teologis, etika filosofis dan moralitas religius.13 W. Poespoprodjo dalam bukunya Filsafat Moral; Kesusilaan dalam Teori dan Praktek, berargumen bahwa moral itu adalah sesuatu yang benarbenar ada dan tidak dapat dipungkiri. Adanya keyakinan tentang moral dan 12 Fadwa El Guindi, Veil: Modesty, Privacy dan Resistance, terj. Mujiburohman “Jilbab: Antara Kesalehan, Kesopanan dan Penawanan”, Jakarta: Serambi, 2003. 13 Majid Fakhry, loc.cit. 24 keharusannya itu bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari, walaupun hal-hal itu kadang kurang nampak dan kurang jelas. Pelanggaran moral bukanlah kesalahan biasa, seperti salah pukul dalam badminton atau salah tendang dalam sepak bola, melainkan sesuatu yang menyangkut manusia sampai sedalam-dalamnya. Jika demikian, maka yang sebaiknya jugalah yang benar, yakni bahwa perbuatan yang baik secara moral itu berupa kebaikan yang sedalam-dalamnya pula. Seperti pelanggaran moral dipandang sebagai sesuatu yang anti perikemanusiaan, demikian juga penataan terhadap moral dilihat sebagai sesuatu yang sesuai sepenuhnya dengan perikemanusiaan yang sejati. Hal inilah yang termuat dalam bahasa dan gagasan sehari-hari. Hampir tidak ada orang yang mau disebut binatang meskipun kelakuannya melebihi binatang.14 Ahmad Amin dalam bukunya, al-Akhlak menyajikan berbagai persoalan etika, mulai dari definisi, aspek-aspek kejiwaan sebagai dasar perilaku (behavior), teori etika dan sejarahnya, dan etika praktis. Ahmad Amin menyebutkan dasar-dasar perilaku secara luas yang meliputi instink, adat kebiasaan, turunan dan lingkungan, kehendak, motif, akhlak, suara hati dan cita-cita. Sayangnya, perilaku yang menjiwai perjuangan Rasulullah dan Khulafa’ al-Rasyidun tidak banyak dikaji, sehingga dasar perilaku hakiki yang menjiwai semangat mereka tidak terlihat.15 14 W. Poespoprodjo, Filsafat Moral; Kesusilaan dalam Teori dan Praktek, Bandung: Pustaka Grafika, 1999. 15 Ahmad Amin, Al-Akhlak, Bandung: Al-Ma’arif, 1996. 25 Sayid Mujtaba Musawi Lari dalam bukunya Etika dan Pertumbuhan Spiritual, banyak mengemukakan bahwa etika erat kaitannya dengan pertumbuhan spiritual. Sebab manusia berbeda dengan binatang, manusia dituntut untuk hidup sesuai dengan asas perilaku yang disepakati secara umum dan harus tahu tentang apa yang baik dan apa yang buruk serta tentang hak dan kewajiban moral, sedangkan binatang tidak. Jika manusia mampu menjalaninya, maka itulah yang disebut manusia yang beretika. Jika tidak, maka jangan heran jika manusia akan bertingkah laku seperti binatang. Banyak fakta membuktikan bahwa dunia ini sudah begitu ramai dengan tingkah-polah binatang berwujud manusia. Mereka tidak memberi kesempatan benih spiritualisme untuk tumbuh dan berkembang, karena yang mereka sirami justru benih-benih hasrat hewaniah yang membunuh spiritualisme dan kemanusiaan.16 Adapun penelitian yang ada kaitannya dengan karakteristik mahasiswa IAIN Waslingo, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Shodiq Abdullah, “Corak Pemikiran Keagamaan Mahasiswa IAIN Walisongo”. Dalam penelitiannya, Shoqid menyimpulkan bahwa sistem pendidikan di IAIN Walisongo agaknya belum mampu membentuk dan menciptakan pribadi mahasiswa yang cenderung berpikir realistik secara maksimal; yaitu pola berpikir yang bersifat faktual, real, logis atau rasional sebagai suatu pendapat yang dapat diterima atau diyakini kebenarannya. Kebanyakan mahasiswa masih berpikir secara autistik, artinya, ersifat mistis atau fatalistik sebagai 16 Sayid Mujtaba Musawi Lari, loc.cit. 26 suatu yang dapat diterima atau diyakini keabsahannya. Padahal IAIN merupakan lembaga pendidikan tinggi Islam yang diharapkan bukan saja mampu mengembangkan diri sebagai lembaga keagamaan tetapi juga mampu memfungsikan diri sebagai lembaga keilmuan. Perbedaan kurikulum di masing-masing fakultas agaknya sangat mempengaruhi corak pemikiran keagamaan mahasiswa.17 Berdasarkan ilustrasi di atas, maka topik yang penulis angkat berbeda dengan lainnya, yang bersifat kasuistik. Oleh karenanya, permasalahan yang penulis angkat mengenai etika religius berbusana mahasiswi layak untuk diangkat. Tanpa sikap a priori, penulis berkesimpulan belum ada penelitian yang secara khusus membahas topik ini. E. Metode Penelitian Penulis akan menitikberatkan pada pengolahan data secara kualitatif. Teknik ini penulis gunakan dengan pertimbangan; pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode ini mendekatkan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. Ketiga, kualitatif lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yag dihadapi.18 Sehinga pola ini lebih tepat dalam penelitian 17 Shodiq Abdullah, “Corak Pemikiran Keagamaan Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang” dalam Jurnal Penelitian Walisongo, Volume I Nomor 2 Nopember 2003. 18 Lexy J. Muleong, Metodelogi Penelitian kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995, hlm. 5. 27 ini, karena untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian jika diharapkan pada persoalan-persoalan tersebut. Secara metodologis, langkah-langkah yang akan penulis tempuh adalah: 1. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yaitu pencarian dan pengumpulan data yang dipergunakan untuk membahas masalah atau problematika dalam penelitiani ini. Dalam pengumpulan data ini menggunakan penulis terjun langsung ke obyek yang akan diteliti. Jenis penelitian semacam ini lazim disebut field research (penelitian lapangan).19 Obyek penelitian ini adalah mahasiswi IAIN Walisongo secara umum, yang kemudian dengan pertimbangan efesiensi, penulis akan melakukan pengacakan pada mahasiswi atau diambil sampelnya saja. Adapun sampel yang diambil adalah mahasiswi yang aktif di beberapa organisasi kemahasiswaan baik di ekstra maupun intra kampus. Berdasarkan tiga pokok permasalahan yang penulis angkat, maka sampel mahasiswi yang diambil ialah mereka yang aktif di organisasi ekstra seperti KAMMI, IMM, HMI dan PMII dan organisasi intra kampus seperti UKM Mawapala, UKM Musik dan UKM Teater. Langkah-langkah yang ditempuh melalui; pertama, observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena- 19 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983, hlm. 22. 28 fenomena yang diselidiki,20 dalam hal ini mahasiswi IAIN Walisongo seperti yang disebutkan di atas. Kedua, wawancara atau interview. Wawancara adalah mencakup cara yang diperlukan seseorang untuk suatu tugas tertentu untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang responden dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu.21 Metode ini digunakan dalam bentuk pertanyaan kepada responden yang bersangkutan. Ketiga, metode angket terskturktur, yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang pilihan jawabannya telah disediakan.22 Metode angket ini sebagai data pendukung saja untuk membantu responden dalam memberikan jawaban. 2. Metode Analisis Data Analisa yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Dalam mendeskripsikan juga mencakup upaya klarifikasi kriteria-kriteria tertentu untuk mengetahui makna yang terkandung dalam data yang telah terkumpul. Kemudian penulis kembangkan untuk membuat prediksi.23 Langkah terakhir dalam penelitian, dalam upaya untuk memperoleh suatu kesimpulan yang akurat, penulis akan menggunakan dua alur pemikiran yaitu induktif dan reflektif. Induktif adalah suatu pola 20 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm. 234. 21 Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: Gramedia, 1983, hlm. 129. 22 Suharsimi Arikunto, op.cit., hlm. 236. 23 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989, hlm. 68-69. 29 pemahaman yang dimulai dengan mangambil kaidah-kaidah yang bersifat khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan reflektif adalah suatu proses berfikir yang mondar-mandir dari data yang satu ke data yang lain.24 F. Sistematika Penulisan Untuk memberikan gambaran yang utuh dan terpadu atas hasil penelitian ini, maka sistematika penulisan tesis ini dibagi dalam lima bab. Adapun rinciannya sebagai berikut: Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang dan perumusan masalah, tujuan penelitian yang sekaligus berfungsi sebagai argumentasi. Selain itu dikemukakan kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab kedua akan memaparkan kajian-kajian mengenai diskursusdiskursus etika sebagai landasan teori. Pada bab ini memuat; istilah etika, norma dasar etika, etika Islam dan norma-normanya, etika berbusana, etika berbusana dilhat dari fungsinya dan seputar kontroversi jilbab. Bab ketiga akan menyajikan etika religius berbusana mahasiswi IAIN Walisongo. Bab ini memuat; potret mahasiswa IAIN Walisongo dan corak keagamaannya, pemahaman etika religius berbusana mahasiswi, sekaligus faktor-faktor apa yang mempengaruhi. 24 Ibid., hlm. 92-93. 30 Bab keempat merupakan analisis. Point-point yang akan dianalisis adalah; analisis terhadap pemahaman etika religius berbusana mahasiswi, analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi etika religius berbusana dan pola ideal etika berbusana mahasiswi IAIN Walisongo. Bab kelima adalah penutup. Hasil pembahasan dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam bagian kesimpulan yang merupakan penegasan jawaban pokok problematika yang diangkat dan asumsi-asumsi yang pernah diutarakan sebelumnya. 31 DAFTAR PUSTAKA Abdullah, Shodiq, “Corak Pemikiran Keagamaan Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang” dalam Jurnal Penelitian Walisongo, Volume I Nomor 2 Nopember 2003. Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, Fiqh Wanita,Bandung: Gema Insani Press, 2002. Al-Zuhaily, Wahbah, Ushul al-Fiqh al-Islami, Jilid I, Beirut: Dâr al-Fikr, 1986. Amin, Ahmad, Al-Akhlak, Bandung: Al-Ma’arif, 1996. Amin, M. Darori, “Norma-norma Etika Islam”, dalam Teologia, Volume 12, Nomor 3, Oktober, 2001. Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 1997. Arman, Sri Rahayu, “Jilbab; Antara Kesucian dan Resistensi”, dalam Http://www.islamlib.com. Tgl. 19 Januari 2003. El Guindi, Fadwa, Veil: Modesty, Privacy dan Resistance, terj. Mujiburohman “Jilbab: Antara Kesalehan, Kesopanan dan Penawanan”, Jakarta: Serambi, 2003. Fakhry, Majid, Ethical Theories in Islam, terj. Zakiyuddin Baidhawi “Etika dalam Islam”, Jakarta: Pustak Pelajar, 1996. Herfanda, Ahmadun Yosi, “Membongkar Ruang Sempit Sastra Religius” dalam Http://www.republika.co.id. Tgl. 1 Agustus, 2004. Koenjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: Gramedia, 1983. Lari, Sayid Mujtaba Musawi, Ethics and Spiritual Growth, terj. M. Hasyim Assagaf ”Etika dan Pertumbuhan Spiritual”, Jakarta: Lentera Basritama, 2001. Muhadjir, Noeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989. Muleong, Lexy J., Metodelogi Penelitian kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995. 32 Musa, Muhammad Yusuf, Filsafat al-Akhlak fi al-Islam, Cairo: Maktabah alKhanji, 1963. Poespoprodjo, W., Filsafat Moral; Kesusilaan dalam Teori dan Praktek, Bandung: Pustaka Grafika, 1999. Salam, Burhanuddin, Etika Individual; Pola Dasar Filsafat Moral, Jakarta: Rineka Cipta, 2000. Suryabrata, Sumadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983. Titus, Harold H., dkk., Persoalan-persoalan Filsafat, Jakarta: Bulan Bintang, 1984. 33 BAB II DISKURSUS-DISKURSUS ETIKA A. Istilah Etika Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Latin ethic yang dalam terjemahan bahasa Inggris kata ethic diartikan dengan “tata susila”.25 Sedangkan secara terminologi, istilah etika menurut Ahmad Amin adalah yang dalam bahasa Gerik disebut ethikos; yaitu a body of moral principles or values, atau kebiasaan, habitat, custom.26 Dengan demikian, dalam pengertian aslinya apa yang disebutkan baik itu ialah yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat (dewasa itu). Lambat laun pengertian etika itu berubah, seperti pengertian sekarang. Etika ialah pengertian yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, seperti mana yang dapat dinilai baik dan mana yang jahat.27 Kronologis penggunaan istilah etika itu dimulai oleh Montaigne (1533-1592), seorang penyair Perancis dalam syair-syairnya yang terkenal pada tahun 1580.28 Istilah lain yang berdekatan etika ialah moral, dan akhlak yang samasama menentukan nilai baik dan buruk sikap dan perbuatan manusia, bahkan terkadang ketiganya berjalan seiring. Menurut Yunahar Ilyas, perbedaan etika, 25 Lihat Markus Willy, dkk., Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, Surabaya: Arloka, 1997, hlm. 172. 26 Lihat Ahmad Amin, Al-Akhlak, terj. Farid Ma’ruf, “Etika”, Bandung: Bulan Bintang, 1975, hlm. 1-3. 27 Lihat Burhanuddin Salam, Etika Individual; Pola Dasar Filsafat Moral, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm. 3. 28 Lihat Frans Magnis Suseno, Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral, Yogyakarta: Kanisius, 1987, hlm. 5. 34 akhlak dan moral terletak pada standar masing-masing. Etika standarnya pertimbangan akal dan pikiran; akhlak standarnya al-Qur’ân dan sunnah, dan moral standarnya adat kebiasaan yang umum berlaku di masyarakat.29 Sedangkan menurut Harold Titus, dkk., perbedaanya hanya dari sudut bahasa, moral berasal dari kata Latin “moralis”, etika berasal dari kata “ethos”, dan akhlak berasal dari bahasa Arab akhlaq, jamak dari khuluq yang berarti budi pekerti. Ketiganya berarti “kebiasaan” atau “cara hidup”.30 Etika sebagai suatu ilmu yang normatif, dengan sendirinya berisi norma (aturan) dan nilai-nilai yang dapat digunakan dalam kehidupan seharihari. Dari segi inilah didapati pemakaian dengan nilai-nilainya yang filosofis. Sementara ilmu yang mempelajari pelaksanaan atau realisasi etika dalam praktek kehidupan sehar-hari itu disebut casuistic; orang yang mempelajarinya disebut casuist.31 Titik tekan penilaian etika sebagai suatu ilmu ialah pada perbuatan baik atau jahat, susila atau tidak susila. Perbuatan atau kelakuan seseorang yang telah menjadi sifat baginya atau telah mendarah daging, itulah yang disebut akhlak atau budi-pekerti. Budi sendiri tumbuhnya dalam jiwa. Apabila telah dilahirkan dalam bentuk perbuatan namanya pekerti.32 Jadi suatu budi 29 Lihat Yunayar Ilyas, Kuliah Akhlak, Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPII), 2004, hlm. 3. 30 Lihat Harold H. Titus, dkk., Persoalan-persoalan Filsafat, Jakarta: Bulan Bintang, 1984, hlm. 141. 31 Lihat Somon Blackburn, Being Good; Pengantar Etika Praktis, terj. Hari Kusharyono, Yogyakarta: Jendela, 2004, hlm. 7. Lihat pula Suparlan Suhartono, Dasar-dasar Filsafat, Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2004, hlm. 16. 32 Lihat Frans Magnis Suseno, op.cit., hlm. 7. Lihat pula M. Amin Abdullah, Filsafat Etika Islam; Antara al-Ghazâlî dan Kant, Bandung: Mizan, 2002, hlm. 67. 35 pekerti, pangkal penilaiannya adalah dari dalam jiwa, semasih menjadi angan, imajinasi, cita, niat hati, sampai ia lahir ke luar berupa perbuatan nyata. Sebenarnya, setiap perbuatan dapat dinilai pada tiga tingkat. Tingkat pertama, semasih belum lahir jadi perbuatan atau masih berupa rencana dalam kata hati, niat. Tingkat kedua, sesudahnya, yaitu sudah berupa perbuatan nyata atau pekerti. Tingkat ketiga, akibat atau hasil dari perbuatan itu; baik atau tidak baik.33 Apa yang masih berupa kata hati atau niat itu, dalam bahasa filsafat ataupun psikologi, biasa disebut karsa atau kehendak, kemauan, will. Isi dari karsa atau kemauan itulah yang akan direalisasikan oleh perbuatan. Langkahlangkah yang ditempuh oleh perbuatan itulah yang dinilai, karenanya dapat digunakan empat variabel; Pertama, tujuannya baik, tetapi cara pencapaiannya tidak baik. Cara pertama ini menggambarkan adanya sesuatu kekerasan. Masalah tujuan tidak perlu dibicarakan lagi, karena sudah jelas baik, yang dinilai sekarang ialah cara mencapainya.34 Kedua, tujuannya tidak baik, tetapi cara mencapainya (kelihatannya) baik, atau tujuannya jahat, tetapi memperolehnya kelihatan baik. Ini menggambarkan bahwa cara yang ditempuh itu tidak fair, tidak sehat tetapi licik, diliputi oleh kepalsuan, penipuan. Cara kerja seperti ini terkenal dalam sejarah sebagai suatu sistem kerja/taktik yang pernah dipakai oleh orang komunis yang menghalalkan 33 Lihat Burhanuddin Salam, op.cit., hlm. 4-5. 34 Sebagai ilustrasi dapat dicontohkan; misalnya seorang pedagang, untuk menyekolahkan anaknya, supaya anak tersebut dapat diterima, ia telah betindak menyuap beberapa orang panitia penguji. Menyekolahkan anak, adalah suatu perbuatan baik. Tetapi jalan yang ditempuhnya itu tidak terpuji. Yang tidak terpuji di sini tentulah kedua belah pihak; yang memberi suap dan yang menerima suap. Lihat Ibid., hlm. 5-6. 36 berbagai cara.35 Ketiga, tujuannya tidak baik, dan cara mencapainya juga tidak baik. Ini menggambarkan bahwa untuk memcapai tujuan yang jahat dan dapat merugikan orang lain, cara apapun ditempuh, misalnya harus menipu, memperdaya atau bahkan sampai membunuh.36 Keempat, tujuannya baik, cara mencapainya juga baik. Cara inilah yang diajarkan oleh etika. Suatu tujuan baik, hendaknya diusahakan pula cara yang baik untuk mencapainya.37 Semenjak zaman Yunani kuno hingga kini, manusia selalu memikirkan prinsip-prinsip tentang masalah mana yang benar dan mana yang salah. Mereka mempunyai ukuran-ukuran dan norma-norma yang berbeda. Suatu tindakan mungkin akan dianggap terpuji di sauatu tempat, akan tetapi di tempat lain dianggap salah atau jahat. Begitu pula suatu perbuatan mungkin dianggap baik di suatu waktu, tetapi dengan berubahnya zaman, perbuatan yang dianggap baik pada masa lampau dianggap jelek pada masa kini. Sebaliknya, suatu perbuatan jahat dan jelek mungkin dianggap baik dan benar pada tempat dan waktu yang berbeda. Hubungan badani sebelum menikah akan dianggap wajar oleh bangsabangsa Barat. Tetapi, bagi orang-orang Timur, khususnya muslim, hal tersebut merupakan perbuatan tercela. Dahulu seorang wanita berpantang keluar dan 35 Sebagai contoh misalnya strategi untuk dapat merebut pemerintahan, mula-mula ditempuhnya taktik kerjasama dengan semua pihak, kelihatannya fair, simpatik. Tetapi suatu saat ia telah merasa dirinya kuat, semua kawan sekerjanya tadi yang tidak seasas dengannya, diterkam. Kasus seperti ini dari segi politik komunis hukumnya biasanya, wajar, tetapi dari segi etiks hukumnya jahat. Lihat Ibid., hlm. 7. 36 Dapat dicontohkan misalnya seorang penjahat, untuk mendapatkan yang tersimpan di bank atau yang merupakan harta kekayaan seseorang, sang perampok tadi tidak akan sayang membunuh jiwa bebrapa orang yang tidak berdosa, yang menghalangi jalannya. Ibid., hlm. 8. 37 Inilah yang ideal, misalnya mau lulus ujian syaratnya harus; belajar bersungguh-sungguh, teliti, disiplin diri, jadi bukan dengan jalan menyogok. Mau membantu mahasiswa untuk lulus, syaratnya ialah memberikan bimbingan secara intensif, aktifkan belajar dengan sungguh hati. Jadi tidak dengan cara menerima sogokan. Itu berarti meracuni jiwa seseorang dan memberikan contoh yang sungguh tidak terpuji bagi seorang pendidik. Ibid. 37 bekerja pada malam hari. Tetapi pada masa industrialisasi sekarang ini, untuk sebagian orang hal tersebut sudah dianggap sebagai hal yang lumrah.38 Dengan demikian dapat ditegaskan lagi bahwa etika ialah suatu yang menentukan nilai baik dan buruk sikap dan perbuatan manusia. Etika sering pula disinonimkan dengan akhlak dan moral. Perbedaannya terletak pada standar masing-masing, namun maksudnya sama, yaitu menentukan nilai baik dan buruk perbuatan manusia. B. Norma Dasar Etika Norma-norma etika dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu norma ekstern dan norma intern. Norma ekstern terdiri atas beberapa paham; pertama, paham pragmatisme. Paham ini menimbang kebaikan dan keburukan suatu perbuatan dari manfaat yang dapat dihasilkan, baik ditinjau dari segi rohani maupun materi dan individu maupun kelompok. Dengan demikian perbuatan yang dianggap baik adalah yang bermanfaat. Semakin besar manfaat suatu perbuatan, semakin tinggi pula nilai kebenarannya.39 Kedua, paham yang mengambil jalan tengah antara dua perbuatan jelek. Norma ini dicetuskan oleh Aristoteles. Menurut paham ini, perbuatan baik adalah yang menjadi jalan tengah antara dua perbuatan yang jelek. Sebagai contoh 38 Lihat Ahmad Mahmud Shubhi, Al-Falsafah al-Akhlaqiyyah fi al-Fikr al-Islami; al‘Aqliyyun wa al-Dzauqiyyun aw al-Nadzar wa al-Amal, Beirut: Dâr al-Nahdhah al-Arabiyah, 1992, hlm. 34. Lihat pula Majid Fakhri, Ethical Theories in Islam, terj. Zakiyuddin Baidhawi “Etika dalam Islam”, Jakarta: Pustak Pelajar, 1996, hlm. 24. 39 Lihat M. Darori Amin, “Norma-norma Etika Islam”, dalam Jurnal Teologia, Volume 12, Nomor 3, Oktober 2001, hlm. 321. 38 kedermawanan adalah baik, karena merupakan jalan tengah antara kikir dan boros. Kesabaran adalah terpuji, karena jalan tengah antara kekerasan dan kelemahan.40 Ketiga, paham yang mengikuti kesesuaian dengan lingkungan. Bagi paham ini, suatu perbuatan diangap baik apabila sesuai dengan lingkungannya. Kesesuaian dengan lingkungan menghasilkan kenikmatan dan kegembiraan, sedengkan ketidak-sesuaian dengan lingkungan menyebabkan penyakit dan kesengsaraan.41 Keempat, paham yang memandang kepada kenyataan dan percobaan. Norma akhlak bagi paham ini merupakan percobaan, yang dengannya akan diketahui baik buruknya suatu perbuatan. Apabila dalam percobaan tersebut dapat dipetik manfaat material maupun spiritual, perbuatan tersebut dapat dikatakan baik. Tetapi apabila tidak, perbuatan itu jelek atau buruk.42 Sedangkan norma intern, dapat didefinisikan sebagai suatu daya yang berasal dari manusia sendiri, yang dengannya manusia bisa membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk. Para pengikut paham ini bersepakat tentang adanya kekuatan bathiniyah di dalam diri manusia untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Daya tersebut dinamakan concience atau dhamir (hati nurani), yang merupakan cermin bagi perbuatan manusia. Dari padanya akan 40 Akan tetapi setelah dilakukan penelitian, banyak yang menganggap bahwa norma ini mengandung kelemahan, karena banyak perbuatan jelek yang tidak ada jalan tengahnya, seperti pree sex, berbohong, menciri dan sebagainya. Lihat Ibid. 41 Lihat Ibid. 42 Lihat Ibid., hlm. 322. 39 terpantul apakah perbuatan tersebut baik atau buruk. Suara hati, bukan saja memberikan informasi tentang baik atau buruknya suatu perbuatan, tetapi memberikan ganjaran kegembiraan bagi yang melakukan baik, dan penyesalan bagi yang melakukan perbuatan jahat.43 Menurut paham rasionalisme, rasio merupakan satu-satunya daya yang dimiliki manusia untuk mengetahui antara yang baik dan yang buruk. Pencetus pendapat ini adalah Socrates dan Plato, yang kemudian dilanjutkan dengan paham Mu’tazilah dalam Islam, dan selanjutnya oleh Imanuel Kant dari Jerman. Paham ini telah menggAbûngkan antara akal dan kehendak baik. Perbuatan baik merupakan perbuatan yang keluar dari kehendak yang baik. Untuk itu, paham ini membuat tiga prinsip bagi seseorang dalam melakukan perbuatan,: pertama, prinisip umum. Jika seseorang akan melakukan suatu perbuatan, hendaknya melakukan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang bisa diterima publik dan telah menjadi undang-undang. Kedua, prinsip penghormatan kepada kemanusiaan dan tidak menjadikannya sebagai alat. Jika seseorang akan melakukan suatu tindakan, hendaknya ia dapat memperlakukan dengan baik kemanusiaan yang ada pada dirinya dan orang lain. Ketiga, kebebasan betindak dari interes dan hasil-hasil dari perbuatan tadi, serta tidak akan tunduk kecuali kepada akal.44 Dari ilustrasi di atas dapat ditegaskan bahwa norma-norma etika dapat dikelompokkan pada norma ekstern dan norma intern. Norma ekstern dibagi pada paham pragmatisme, paham jalan tengah antara dua perbuatan baik dan jelek, 43 Lihat Harry Hamersma, Tokoh-tokoh Filsafat Barat Modern, Jakarta: Gramedia, 1986, hlm. 90. 44 Ibid., hlm. 93. 40 paham yang mengikuti kesesuaian dengan lingkungan dan paham yang memandang kepada kenyataan dan percobaan. Sedangkan norma intern ialah suatu daya yang berasal dari manusia sendiri yang menggunakan beberapa prinsip; prinsip umum, prinsip penghormatan kepada kemanusiaan dan prinsip kebebasan betindak. C. Etika Islam dan Norma-normanya Kalau di atas telah disebutkan pengertian etika secara umum, perlu pula disebutkan di sini pengertian etika Islam. Pengertian etika Islam ialah; “prinsipprinsip serta kaidah-kaidah yang disusun untuk perbuatan-perbuatan manusia yang telah digariskan oleh wahyu, untuk mengatur kehidupan mereka dan mencapai tujuan dari keberadaan mereka di dunia ini dengan cara yang sebaikbaiknya”.45 Artinya, prinsip-prinsip atau aturan yang mengaturan perbuatan baik dan buruk yang menurut Toshihiko Izutzu disebut oleh al-Qur’ân dengan shalih dan tidak shalih, dalam bahasa Inggrisnya disebut righteous (sepantasnya). Kata shalih ini selalu berdekatan penyebutannya dengan kata iman, karenanya memiliki hubungan semantik yang mengikat.46 Perbedaan pokok etika Islam dan etika yang lainnya terletak pada sumber. Sumber utama dari etika secara umum ialah penilaian manusia, karenanya bersifat relatif. Sedangkan sumber utama dari etika Islam adalah wahyu 45 Lihat Muhammad Yusuf Musa, Filsafat al-Akhlaq fi al-Islam, Cairo: Maktabah al-Khanji, 1963, hlm. 54. 46 Lihat Toshihiko Izutzu, Ethico-Religious Concepts in the Qur’an, terj. Agus Fahri Husein “ Konsep Etika Religius dalam al-Qur’ân, Yogyakarta: Tiara Wacana, 3003, hlm. 246. 41 yang datang dari Allah S.W.T. dan Nabi Muhamamd s.a.w. Karena sumbernya wahyu, maka sumber etika Islam bersifat mutlak. Wahyu merupakan sumber utama etika Islam. Sumber utama ini kemudian dikembangkan menjadi tiga; al-Qur’ân dan al-Sunnah, kemauan yang baik dan tujuan, akal dan hati nurani. Kesemuanya saling melengkapi dan terkait, sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Al-Qur’ân dan al-Sunnah Al-Qur’ân yang diturunkan kepada umat manusia antara lain untuk dijadikan petunjuk dan pembeda antara yang baik dan yang salah. Dalam al-Qur’ân dijumpai petunjuk-petunjuk bagaimana seorang muslim itu harus berhubungan dengan sesama manusia serta bagaimana pula caracara mereka memperlakukan alam ini dan manfaatnya. Ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk selalu mengikuti petunjuk-petunjuk al-Qur’ân antara lain terdapat dalam surat al-Nisâ’ ayat 59 yang berbunyi: ن ْ ل َوأُوﻟِﻲ ا ْﻟ َﺄ ْﻣ ِﺮ ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ َﻓِﺈ َ ﻦ ءَا َﻣﻨُﻮا َأﻃِﻴﻌُﻮا اﻟﱠﻠ َﻪ َوَأﻃِﻴﻌُﻮا اﻟ ﱠﺮﺳُﻮ َ ﻳَﺎَأ ﱡﻳﻬَﺎ اﱠﻟﺬِﻳ ن ﺑِﺎﻟﱠﻠ ِﻪ وَا ْﻟ َﻴ ْﻮ ِم َ ن ُآ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ُﺗ ْﺆ ِﻣﻨُﻮ ْ ل ِإ ِ ﻲ ٍء َﻓ ُﺮدﱡو ُﻩ ِإﻟَﻰ اﻟﱠﻠ ِﻪ وَاﻟ ﱠﺮﺳُﻮ ْ ﺷ َ ﻋ ُﺘ ْﻢ ﻓِﻲ ْ َﺗﻨَﺎ َز .َﺗ ْﺄوِﻳﻠًﺎ ﻦ ُﺴ َﺣ ْ ﺧ ْﻴ ٌﺮ َوَأ َ ﻚ َ ﺧ ِﺮ َذِﻟ ِ اﻟْﺂ Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu 42 berlainan pendapat tentnag sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah (al-Qur’ân) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. al-Nisâ’ (4): 59).47 Kemudian pada ayat 105 disebutkan: ن َ ن َآﻤَﺎ َﺗ ْﺄَﻟﻤُﻮ َ ن َﻓِﺈ ﱠﻧ ُﻬ ْﻢ َﻳ ْﺄَﻟﻤُﻮ َ ن َﺗﻜُﻮﻧُﻮا َﺗ ْﺄَﻟﻤُﻮ ْ َوﻟَﺎ َﺗ ِﻬﻨُﻮا ﻓِﻲ ا ْﺑ ِﺘﻐَﺎ ِء ا ْﻟ َﻘ ْﻮ ِم ِإ .ﺣﻜِﻴﻤًﺎ َ ﻋﻠِﻴﻤًﺎ َ ن اﻟﱠﻠ ُﻪ َ ن َوآَﺎ َ ﻦ اﻟﱠﻠ ِﻪ ﻣَﺎ ﻟَﺎ َﻳ ْﺮﺟُﻮ َ ن ِﻣ َ َو َﺗ ْﺮﺟُﻮ Artinya : “Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang kianat”. (Q.S. al-Nisâ’ (4): 105). 48 Surat al-Isra’ ayat 9 menyebutkan: 47 Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur’ân, al-Qur’ân dan Terjemahnya, Madinah: Mujamma’ al-Malik Fahd li Thiba’at Mushaf al-Syarif, 1418 H., hlm. 128. 48 Ibid., hlm. 139. 43 ﺧﺒِﻴﺮًا َ ﻋﺒَﺎ ِد ِﻩ ِ ب ِ ﻚ ِﺑ ُﺬﻧُﻮ َ ح َو َآﻔَﻰ ِﺑ َﺮ ﱢﺑ ٍ ﻦ َﺑ ْﻌ ِﺪ ﻧُﻮ ْ ن ِﻣ ِ ﻦ ا ْﻟ ُﻘﺮُو َ َو َآ ْﻢ َأ ْهَﻠ ْﻜﻨَﺎ ِﻣ َﺑﺼِﻴﺮًا Artinya : “Sesunguhnya al-Qur’ân itu memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lurus dan memberi kabar gembira keapda orangorang mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar”. (Q.S. al-Isra’ (17): 9)49. Sedangkan perintah untuk mengikuti al-Sunnah, karena salah satu misi diutusnya Nabi Muhammad s.a.w. adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sabdanya: “Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyermpurnakan akhlak” (hadîts diriwayatkan oleh Imam Malik).50 Akhlak Nabi sendiri merupakan aktualisasi dari akhlak al-Qur’ân. Aisyah r.a. berkata: “Akhlak Nabi adalah al-Qur’ân”. (H.R. Muslim).51 Oleh karenanya, Nabi Muhammad itu menjadi teladan dan panutan bagi semua muslim. Secara umum, akhlak yang digariskan al-Qur’ân dapat dirinci menjadi: iman kepada Allah, ikhlas, kejujuran, melaksanakan amanat dan menepati janji, memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran. 49 Ibid., hlm. 425-426. 50 Lihat Muhammad al-Ghazâlî, Khuluq al-Muslim, Cairo: Dâr al-Kutub al-Hadîtsash, 1974, hlm. 7. 51 Muslim ibn Hajaj, Shahîh Muslim, Juz I, Beirut: Dâr al-Ilm, t.th., hlm. 47. 44 Kemudian berusaha mencapai hal yang baik dan mulia, tolong-menolong dalam kebaikan, tekun dalam melakukan sesuatu, lurus dan moderat, mengikuti perbuatan-perbuatan baik dan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan jahat dan sebaginya.52 Ibadat-ibadat yang disyari’atkan dalam Islam, bukan hanya peribadatan-peribadatan yang tidak bisa dipahami, tetapi menjadi ikatan antara manusia dengan hal-hal ghaib yang tidak bisa diketahuinya. Selain itu berfungsi sebagai latihan dalam membiasakan manusia untuk hidup secara rasional, konsisten dalam setiap kondisi.53 2. Kemauan Baik dan Tujuan Sebetulnya norma ini sudah tercakup dalam norma al-Qur’ân dan al-Sunnah, yakni semua perbuatan itu haruslah didasarkan pada keikhlasan, yaitu hanya mengharapkan keridhaan Allah semata. Tetapi karena pentingnya norma ini, maka perlu ada bahasan tersendiri. Kemauan seseorang dapat menentukan baik buruknya suatu perbuatan. Kalau wujud perbuatan itu jelak tetapi niatnya baik, dianggaplah suatu perbuatan yang baik. Tetapi sebaliknya, apabila niatnya tidak baik, perbuatan itu dianggap jelek. Begitu pula dalam etika Islam. 52 Lihat Muhammad al-Ghazâlî, op.cit., hlm. 90. Lihat pula Toshihiko Izutsu, EthicoReligious Concepts in the Qur’an, terj. Mansuruddin Djoely “Etika Beragama dalam Qur’an”, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993, hlm. 26, dst. 53 Lihat Miqdad Yalchan, al-Ittijah al-Akhlaqi fi al-Islam, Cairo: Maktabah al-Khanji, 1973, hlm. 273-277. 45 Islam tidak sekadar melihat baik buruknya wujud suatu perbuatan, tetapi juga melihat dari niat yang menyebabkan timbulnya perbuatan itu. Rasul bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak melihat tubuh-tubuh, dan bentukbentukmu, tetapi kepada hatimu” (H.R. Bukhari).54 Di dalam hadîts yang lain Rasûlullâh bersabda: “Mata manusia itu ibarat petunjuk, telinga dan lidahnya penerjemah, kedua tangannya sayap, kedua kakinya utusan dan hatinya adalah raja. Apabila raja itu baik, tentara-tentaranya baik. Kalau demikian peranan hati, wajib diawasi untuk dicuci dari hal-hal yang mengotorinya” (H.R. Muslim).55 Karena persoalan niat, Allah mencela orang yang melakukan shalat tetapi disertai riya, yakni orang yang berniat dalam shalatnya itu agar dilihat orang lain (Q.S. al-Ma’un (107): 4-6).56 Begitu pula Rasûlullâh pernah mengecam orang yang hijrah ke Yatsrib, karena hijrahnya bukan memenuhi perintah Allah dan Rasul-Nya, tetapi karena melaksanakan permintaan calon isteri yang akan dinikahinya. Walaupun hijrah merupakan perbuatan yang mulia dan baik, tetapi karena niatnya yang salah, rasul mengecam hijrah tersebut dengan sabdanya: “Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung kepada niatnya dan sesungguhya setiap orang akan mendapat balasan sesuai niatnya”. (H.R. Bukhari).57 54 Muhammad bin Ismail al-Bukhâri, Shahîh Bukhari, Juz I, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th., hlm. 67. 55 Muslim Ibn Hajaj, op.cit., Juz I, hlm. 14. 56 Lihat Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur’ân, op.cit., hlm. 1108. 57 Lihat al-Bukhâri, op.cit., Juz I, hlm. 57. 46 Bagi orang muslim, sebelum melakukan perbuatan diperintahkan untuk membaca basmalah. Perintah ini bukan berarti perintah untuk meminta berkah dan pertolongan melalui bacaan ini, tetapi merupakan perintah dan petunjuk bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah karena Allah S.W.T. dan hanya diperuntukkan kepada-Nya. Setelah perbuatan tersebut didasari dengan niat yang baik, sebagai pengabdian kepada Allah S.W.T., maka perbuatan orang tersebut mempunyai tujuan utama, meraih kebahagiaan ukhrawi.58 3. Hati Nurani Norma ini merupakan daya asli manusia yang membuat seseorang itu merasa lega apabila melakukan perbuatan baik, dan menyesal apabila melakukan perbuatan jahat. Oleh karenanya, Islam mengakui norma ini, dan menetapkannya sebagai salah satu norma-norma etika Islam. Di dalam jiwa manusia itu terdapat dua kekuatan yang saling tarik menarik dalam berbuat. Yang menarik kebaikan adalah hati nurani, dan yang menarik kepada kejahatan adalah hawa nafsu. Terkait dengan persoalan hati nurani, Allah S.W.T. berfirman: 58 Abû Hamid al-Ghazâlî, al-Munqidh min al-Dhalal, Istambul: Hakikat Kitabevi, 1984, hlm. 9. 47 َو َﻗ ْﺪ,ﻦ َزآﱠﺎهَﺎ ْ ﺢ َﻣ َ َﻗ ْﺪ َأ ْﻓَﻠ, َﻓَﺄ ْﻟ َﻬ َﻤﻬَﺎ ُﻓﺠُﻮ َرهَﺎ َو َﺗ ْﻘﻮَاهَﺎ,ﺳﻮﱠاهَﺎ َ ﺲ َوﻣَﺎ ٍ َو َﻧ ْﻔ... … ﻦ َدﺳﱠﺎهَﺎ ْ ب َﻣ َ ﺧَﺎ Artinya : “Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya, sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya” (Q.S. al-Syams: (91): 7-10).59 Karenanya, hati nurani menepati posisi penting dalam etika Islam. Rasûlullâh s.a.w. bersabda dalam mempertegas posisi hati nurani: “Kebaikan itu ialah yang memberikan ketenangan kepada jiwa dan hatimu, dan kejahatan itu adalah yang terbetik di dalam hatimu dan yang menimbulkan gejolak di dalamnya, walaupun banyak orang yang memberitahuan kepadamu” (H.R. Muslim).60 Sabdanya pula: “Tinggalah apa yang meragukanmu dan ambillah apa yang tidak merugikanmu” (H.R. Abû Dawud).61 Hati nurani ini ada pada setiap manusia, baik tua, muda, dewasa atau anak terpelajar sampai anak yang kurang ajar sekalipun. Apabila ada 59 Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur’ân, op.cit., hlm. 1064. 60 Muslim Ibn Hajaj, op.cit., Juz I, hlm. 89. 61 Abû Dawud, Sunan Abû Dawud, Juz III, Beirut Libanon: Dâr al-Ilmiah, t.th., hlm. 16. 48 anak kecil berbuat suatu kesalahan, ia akan merasa malu, gelisah dan perasaan-persaaan tidak enak lainnya. Perasaan ini ada pada setiap orang dan berjenjang menurut pendidikannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi pula tingkat suara hatinya. Oleh karenanya suara ini perlu dididik dengan pendidikan moral yang baik.62 Karena hidup manusia sangat tergantung dan selalu dipengeruhi oleh ruang dan waktu, tidaklah aneh bahwa suara hati masing-masing pribadi kadang-kadang berbeda antara satu pribadi dengan lainnya. Perbedaan itu pula saling pengaruh-mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena diperlukan kekokohan nurani yang tidak mudah terpengaruh oleh suasana lingkungan.63 Dari ilustrasi di atas dapat ditegaskan lagi bahwa yang dimaksud etika Islam ialah prinsip-prinsip serta kaidah-kaidah yang disusun untuk perbuatanperbuatan manusia yang telah digariskan oleh wahyu. Perbedaan etika Islam dengan etika lainnya ialah terletak pada sumber yang digunakan. Jika etika secara umum sumbernya penilaian manusia sendiri, maka etika Islam bersumber dari wahyu atau al-Qur’ân dan hadîts. D. Etika Berbusana 62 Miqdad Yalchan menandaskan bahwa dengan pendidikan moral yang baik, akan tercipta pribadi-pribadi muslim yang baik, kalau tercipa pribadi-pribadi muslim yang baik, maka akan tercipta masyarakat muslim yang baik, dan dengan demikian akan tercipta kebudayaan Islam yang baik pula. Lihat Miqdad Yalchan, op.cit., hlm. 43. 63 W. Poespoprodjo, Filsafat Moral; Kesusilaan dalam Teori dan Praktek, Bandung: Pustaka Grafika, 1999, hlm. 153, dst. 49 Sebelumnya perlu dikemukanan terlebih dahulu apa yang dimaksud busana. Kata busana biasa disinonimkan dengan kata pakaian, yaitu sesuatu yang dipakai untuk menutup tubuh.64 Fungsi busana ialah tergantung si pemakainya, karenanya ada yang cukup menggunakan busana atau pakaian untuk menutup badannya, ada pula yang memerlukan pelengkap seperti tas, topi, kaos kaki, selendang, dan masih banyak lagi yang menambah keindahan dalam berbusana.65 Menurut kamus bahasa Arab, busana atau pakaian mempunyai banyak muradlif (sinonim) seperti libas bentuk jamak dari lubs yang berasal dari fi’il madhi: labisa-yalbasu yang artinya memakai, atau tsiyabûn jamak dari tsaub yang artinya pakaian, juga disebut sirbalun yang jamaknya saraabiil, artinya juga baju atau pakaian.66 Saraabiil dapat pula diartikan gamis atau baju kurung (jubah).67 Di atas telah disebutkan bahwa Islam memberikan sandaran etika kepada wahyu, karenanya permasalahan etika tidak dapat dipisahkan dari keyakinan kaum muslimin terhadap eksistensi Tuhan Yang Maha Esa, yang mutlak dan transenden, serta syari’ahnya yang kokoh, sebagaimana hal itu juga terdapat pada agama lain.68 Tuhan, menurut keyakinan mereka tidak 64 Lihat Tim Penyusun Kamus Dekdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jaakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm. 637. 65 Lihat Lisyani Affandi, Tata Busana 3, Bandung: Ganeka Exact, 1996, hlm. 69. 66 Lihat Ibn Mandhur, Lisan al-Arab, Mesir: Dâr al-Ma’arif, t.th., hlm. 1983. 67 Lihat Ahmad Warson Munawir, Kamus al-Munawir Arab-Indonesia, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir Krapyak, 1984, hlm. 665. 68 Pada dasarnya, fitrah manusia sebagai mahluk yang memiliki hati nurani, adalah religius. Seorang bayi mungil akan diam sejenak ketika mendengar suara adzan dari masjid maupun 50 hanya sebagai pencipta (al-Khaliq) tetapi juga sebagai pembimbing atau petunjuk bagi perjalanan sejarah dan pengatur segala bentuk keteraturan alam semesta. Atau Tuhan juga sebagai al-Mudabbir (pengatur) dan al-Rabb (pembimbing, pendidik) bagi seluruh alam. Karena tekanan etika perbuatan manusia, etika Islam juga memperhatikan pola hubungan dan perbuatan. Dikenalah apa yang disebut “etika Islami”. Seperti cara bergaul, duduk, berjalan, makan-minum, tidur, dan pola berbusana. Artinya, ada patokan-patokan yang harus diikuti. Seperti dalam pola berbusana, menurut Ibrahim Muhammad Al-Jamal dalam bukunya, Fiqh Wanita, mengatakan; seorang muslimah dalam berbusana hendaknya memperhatikan patokan; menutupi seluruh tubuh selain yang bukan aurat yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Tidak ketat sehingga masih menampakkan bentuk tubuh yang ditutupinya. Tidak tipis menerawang sehingga warna kulit masih bisa terlihat. Tidak menyerupai pakaian lelaki Tidak berwarna menyolok sehingga menarik perhatian orang.69 Patokan-patokan pola berbusana muslimah tersebut sampai saat ini masih menjadi perdebatan, utamanya jilbab. Apakah ia mencirikan kesalehan televisi, karena gelombang getaran suara adzan menyambung dengan getaran hati nurani sang bayi. Hati nurani adalah 'danau religiusitas' tempat suara-suara religiusitas bersemayam, dan sering hanya dapat didengar kalau seseorang bisa merenung dalam sepi dan sendiri. Karena itulah, Nabi perlu menyepi di Gua Hira, melepaskan diri dari kegalauan peradaban jahiliyah, untuk dapat mendengarkan suara hati nuraninya dan menerima kabar kebenaran sejati. Umat lain pun melakukan metode serupa untuk mendengar bisikan nurani dan menerima bersitan cahaya Tuhan. Lihat Ahmadun Yosi Herfanda, “Membongkar Ruang Sempit Sastra Religius” dalam Http://www.republika.co.id. Tgl. 1 Agustus, 2004. 69 Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fiqh Wanita,Bandung: Gema Insani Press, 2002, hlm. 130 51 atau hanya sebatas identitas wanita muslimah. Jika jilbab dianggap sebagai pola busana muslimah, maka perlu ditelusuri lebih dalam dan bahasan khusus. Menurut M. Quraisy Shihab, al-Qur’ân sendiri sebagai sandaran etika Islam, paling tidak menggunakan tiga istilah untuk busana (pakaian), yaitu libas, tsiyab, dan sarabil. Libas pada mulanya berarti penutup-apa pun yang ditutup. Fungsi pakaian sebagai penutup amat jelas. Tetapi, tidak harus berarti “menutup aurat”, karena cincin yang menutup sebagian jari juga disebut libas, dan pemakainya ditunjuk dengan menggunakan akar katanya. Kata libas digunakan oleh al-Qur’ân untuk menunjukkan pakaian lahir maupun batin, sedangkan kata tsyiyab digunakan untuk menunjukkan pakaian lahir. Kata ini terambil dari kata tsaub yang berarti kembali, yakni kembalinya sesuatu pada keadaan semula, atau pada keadaan yang seharusnya sesuai dengan ide pertamanya. 70 Selain kata tersebut ada istilah lain yang lebih mendekati pada makna pakaian muslimah yaitu jilbab dan hijab. Kebanyakan para ulama memilih jilbab untuk istilah busana muslimah, dan sedikit yang menggunakan istilah hijab.71 Ungkapan yang menyatakan bahwa ide dan akhirnya adalah kenyataan, mungkin dapat membantu memahami pengertian kebehasaan tersebut. Ungkapan ini berarti kenyataan harus dikembalikan kepada ide asal, karena kenyataan adalah cerminan dari ide asal. Ide dasar tentang pakaian 70 Kata libas ditemukan sebanyak sepuluh kali, tsiyab ditemukan sebanyak delapan kali, sedangkan sarabil ditemukan sebanyak tiga kali dalam dua ayat. Lihat M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’ân, Bandung: Mizan, 1998, hlm. 155-156.. 71 Ahmad al-Hajji al-Kurdi, Hukum-hukum Wanita dalam Fiqh Islam, Surabaya: Dimas, t.th., hlm. 163-164. 52 menurut al-Raghib al-Isfahani menyatakan bahwa pakaian dinamai tsiyab atau tsaub, karena ide dasar adanya bahan-bahan pakaian adalah agar dipakai. Jika bahan-bahan tersebut setelah dipintal kemudian menjadi pakaian, maka pada hakikatnya ia telah kembali pada ide dasar keberadaannya.72 Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa karena etika Islam mencakup segala perbuatan dan tingkah laku manusia, maka diatur pula pola berbusana. Karenanya, ada patokan-patokan yang harus diikuti dalam memakai busana menutupi, yaitu menutup aurat, tidak ketat, tidak tipis dan menerawang. E. Etika Berbusana; Tinjauan Fungsi Mengenai fungsi busana (pakaian), menurut M. Quraisy Shihab setidaknya ada empat fungsi jika merujuk pada al-Qur’ân, yaitu sebagai penutup aurat, sebagai perhiasan, sebagai perlindungan atau ketakwaan, dan sebagai identitas. Misalnya yang disebutkan dalam surat al-A’raf (7): ayat 26: ﺧ ْﻴ ٌﺮ َ ﻚ َ س اﻟ ﱠﺘ ْﻘﻮَى َذِﻟ ُ ﺳﻮْﺁ ِﺗ ُﻜ ْﻢ َورِﻳﺸًﺎ َوِﻟﺒَﺎ َ ﻋَﻠ ْﻴ ُﻜ ْﻢ ِﻟﺒَﺎﺳًﺎ ُﻳﻮَارِي َ ﻳَﺎ َﺑﻨِﻲ ءَا َد َم َﻗ ْﺪ َأ ْﻧ َﺰ ْﻟﻨَﺎ ن َ ت اﻟﱠﻠ ِﻪ َﻟ َﻌﱠﻠ ُﻬ ْﻢ َﻳ ﱠﺬ ﱠآﺮُو ِ ﻦ ءَا َﻳﺎ ْ ﻚ ِﻣ َ َذِﻟ Artinya : “Wahai putra-putri Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kamu pakaian yang menutup auratmu dan 72 Al-Raghib al-Isfahani, Mu’jam al-Mufradat Alfadz al-Qur’ân, disunting oleh Nadim Mars’ashli, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th., hlm. 70. 53 juga (pakaian) bulu (untuk menjadi perhiasan), dan pakaian takwa itulah yang paling baik” (Q.S. al-A’raf (7): 26).73 Menurut M. Quraisy Shihab ayat ini setidaknya menjelaskan dua fungsi pakaian, yaitu penutup aurat dan perhiasan. Sebagian ulama bahkan menyatakan bahwa ayat di atas berbicara tentang fungsi ketiga pakaian, yaitu fungsi takwa dalam arti pakaian dapat menghindarkan seseorang terjerumus ke dalam bencana dan kesulitan, baik bencana duniawi maupun ukhrawi.74 Ada pula ayat lain yang menjelaskan fungsi ketiga pakaian, yakni pemelihara dari sengatan panas dan dingin. Di dalam al-Qur’ân disebutkan: … ل َأ ْآﻨَﺎﻧًﺎ ِ ﺠﺒَﺎ ِ ﻦ ا ْﻟ َ ﻞ َﻟ ُﻜ ْﻢ ِﻣ َ ﺟ َﻌ َ ﻇﻠَﺎﻟًﺎ َو ِ ﻖ َ ﺧَﻠ َ ﻞ َﻟ ُﻜ ْﻢ ِﻣﻤﱠﺎ َ ﺟ َﻌ َ وَاﻟﱠﻠ ُﻪ Artinya : “Dia (Allah) menjadikan untuk kamu pakaian yang memelihara kamu dari sengatan panas (dan dingin), serta pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan …” (Q.S. al-Nahl (16): 81).75 Fungsi pakaian selanjutnya diisyaratkan oleh al-Qur’ân surat alAhzâb (33) 59 yang menugaskan Nabi s.a.w. agar menyampaikan kepada 73 Tim Penyelnggara Penterjemah al-Qur’ân, op.cit., hlm. 224. 74 Lihat M. Quraish Shihab, op.cit., hlm. 160. 75 Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur’ân, op.cit., hlm. 414. 54 isteri-isterinya, anak-anak perempuannya serta wanita-wanita mukmin agar mereka mengulurkan jilbab mereka: ﻦ ﺟﻠَﺎﺑِﻴ ِﺒ ِﻬ ﱠ َ ﻦ ْ ﻦ ِﻣ ﻋَﻠ ْﻴ ِﻬ ﱠ َ ﻦ َ ﻦ ُﻳ ْﺪﻧِﻴ َ ﻚ َو ِﻧﺴَﺎ ِء ا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨِﻴ َ ﻚ َو َﺑﻨَﺎ ِﺗ َﺟ ِ ﻞ ِﻟَﺄ ْزوَا ْ ﻲ ُﻗ ﻳَﺎَأ ﱡﻳﻬَﺎ اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱡ ... ﻦ َ ﻦ َﻓﻠَﺎ ُﻳ ْﺆ َذ ْﻳ َ ن ُﻳ ْﻌ َﺮ ْﻓ ْ ﻚ َأ ْدﻧَﻰ َأ َ َذِﻟ Artinya : “Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu, dan isteri-isteri orang mukmin; “hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal, sehingga mereka tidak diganggu (oleh lidah/tangan usil)” (Q.S. al-Ahzâb (33): 59).76 Untuk memahami kembali fungsi-fungsi busana, dapat diperjelas lagi ilustrasi berikut: 1. Busana Sebagai Penutup Aurat Aurat dalam al-Qur’ân disebut sau’at yang terambil dari kata sa’a, yasu’u yang berarti buruk, tidak menyenangkan. Kata ini sama maknanya dengan aurat yang terambil dari kata ar yang berarti onar, aib, tercela. Keburukan yang dimaksud tidak harus dalam arti sesuatu yang pada dirinya buruk, tetapi bisa juga karena adanya faktor lain yang 76 Ibid., hlm. 678. 55 mengakibatkannya buruk. Tidak satu pun dari bagian tubuh yang buruk karena semuanya baik dan bermanfaat termasuk aurat. Tetapi bila dilihat orang, maka “keterlihatan” itulah yang buruk.77 Tentu saja banyak hal yang sifatnya buruk, masing-masing orang dapat menilai. Agama pun memberi petunjuk tentang apa yang dianggapnya aurat atau sau’at. Dalam fungsinya sebagai penutup, tentunya pakaian dapat menutupi segala yang enggan diperlihatkan oleh pemakai, sekalipun seluruh badanya. Tetapi dalam konteks pembicaraan tuntunan atau hukum agama, aurat dipahami sebagai anggota badan tertentu yang tidak boleh dilihat kecuali oleh orang-orang tertentu.78 Bukan hanya kepada orang tertentu selain pemiliknya, Islam tidak “senang” bila aurat, khususnya aurat besar (kemaluan) dilihat oleh siapapun, seperti yang telah disebutkan bahwa ide dasar aurat adalah “tertutup atau tidak dilihat walau oleh yang bersangkutan sendiri”.79 Dalam sebuah hadîts disebutkan: “Hindarilah telanjang, karena ada (malaikat) yang selalu bersama kamu, yang tidak pernah terpisah denganmu kecuali ketika ke kamar belakang dan ketika seseorang berhubungan seks dengan isterinya. Maka malulah kepada mereka dan hormatilah mereka”. (H. R. al-Turmudzî).80 Dalam sebuah hadîts yang diriwayatkan oleh Ibn Majah disebutkan: “Apabila seseorang di antara 77 Lihat M. Quraish Shihab, Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2004, hlm. 35, dst. 78 Lihat M. Qurasih Shihab, Wawasan … op.cit., hlm. 163. 79 Al-Raghib al-Isfahani, loc.cit. 80 Al-Turmudzî, Sunan al-Turmudzî, Juz I, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th., hlm. 57. 56 kamu berhubungan seks dengan pasangannya, jangan sekali-kali keduanya telanjang bagaikan telanjangnya binatang”. (H.R. Ibn Majah).81 Tampak jelas bahwa yang dikemukakan di atas merupakan tuntutan moral. Sedangkan tuntutan hukumnya tentunya lebih longgar. Dari segi hukum, tidak terlarang bagi seseorang bila sendirian atau bersama isterinya untuk tidak berpakaian. Tetapi, ia berkewajiban menutup auratnya, baik aurat besar (kemaluan) maupun aurat kecil, selama diduga akan ada seseorang selain pasangannya yang mungkin melihat. Ulama sepakat menyangkut kewajiban berpakaian sehingga aurat tertutup, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang batas aurat itu. Bagian mana dari tubuh manusia yang harus selalu ditutup. Imam Malik, Syafi’î, dan Abû Hanifah berpendapat bahwa lelaki wajib menutup seluruh badannya dari pusar hingga lututnya, meskipun ada juga yang berpendapat bahwa yang wajib ditutup dari anggota tubuh lelaki hanya yang terdapat antara pusat dan lutut yaitu alat kelamin dan pantat. Sedangkan mengenai aurat wanita, terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama klasik sendiri, secara garis besar pendapatnya mengenai aurat wanita terbagi pada dua kelompok besar. Yang pertama menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita tanpa kecuali adalah aurat, sehingga harus diutupi. Kelompok kedua mengecualikan wajiah dan tepapak tangan. Ada 81 Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Juz I, Beirut: Dâr al-Firk, t.th., hlm. 69. 57 juga yang menambahkan dengan sedikit longgar, seperti Abû Hanifah yang menambahkan kaki wanita juga boleh terbuka.82 Adapun pandangan ulama kontemporer dalam menyikapi aurat wanita, sudah beragam. Ada yang masih berpadangan seperti ulama klasik bahwa busana wanita harus menutup seluruh badan karena seluruh badan wanita adalah aurat, atau ada yang mengecualikan muka dan telapak kaki. Kemudian pandangan yang mengatakan bahwa tidak ada satu ketetapan agama (syari’at) yang mengatur batas-batas aurat wanita. Qasim Amin adalah salah satu cendikiawan kontemporer yang berpendapat demikian. Menurut, wanita tidak perlu memakai pakaian khusus seperti jilbab. Kemudian Muhammad Shahrur yang berpendapat bahwa “pakaian tertutup yang kini dinamai jilbab (hijab) bukanlah kewajiban agama tetapi ia adalah satu bentuk pakaian yang dituntut oleh kehidupan bermasyarakat dan lingkungan serta dapat berubah dengan perubahan masyarkat. Sebab, pada zaman Nabi dan sesudahnya, pola berbusana muslimah juga sangat beragam. Pola berbusana wanita merdeka seperti Khadijah, isteri Nabi berbeda dengan lainnya. Atau pakaian para wanita yang menjadi budak juga beragam. Status sosial juga sangat mempengaruhi pola berbusana wanita ketika itu. 83 82 Salah satu sebab perbedaan pendapat ini adalah perbedaan penafsiran terhadap maksud firman Allah dalam surat al-Nûr (24) yang artinya: “Dan janganlah mereka menampakan perhiasannya kecuali yang tampak darinya”. Lihat Abd al-Rahman al-Jaziri, al-Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th., hlm. 60. Lihat pula M. Quraish Shihab, Jilbab … op.cit., hlm. 52. 83 Lihat Muhammad Shahrur, Metodologi Fiqh Islam Kontemporer, terj. Yogyakarta: Elsaq, 2004, hlm. 485-487. 58 Karena fungsinya sebagai penutup aurat, maka dalam berbusana menurut M. Quraish Shihab ada yang harus diperhatikan agar pola berbusana tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai etika ajaran Islam. Pertama, tidak boleh tabarruj. Maksudnya, tidak boleh menampakkan “perhiasan” dalam pengertian yang umum yang biasanya tidak dinampakkan oleh wanita baik-baik, atau memakai sesuatu yang tidak wajar dipakai. Seperti ber-make up secara berlebihan, berbicara secara tidak sopan atau berjalan dengan berlenggak-lenggok dan segala macam sikap yang mengundang perhatian laki-laki. Menampakkan sesuatu yang biasanya tidak dinampakkan kecuali kepada suami dapat mengundang decak kagum laki-laki lain yang dapa gilirannya dapat menimbulkan rangsangan atau mengakibatkan gangguan dari yang usil.84 Di dalam alQur’ân disebutkan: ...ﻇ َﻬ َﺮ ِﻣ ْﻨﻬَﺎ َ ﻦ ِإﻟﱠﺎ ﻣَﺎ ﻦ زِﻳ َﻨ َﺘ ُﻬ ﱠ َ َوﻟَﺎ ُﻳ ْﺒﺪِﻳ... Artinya : “ … Janganlah mereka menampakkan hiasan mereka kecuali apa yang nampak darinya …” (Q.S. al-Nûr (24) : 31).85 Kedua, tidak boleh mengundang perhatian laki-laki. Segala bentuk pakaian, gerak-gerik dan ucapan, serta aroma yang bertujuan atau dapat mengundang rangsangan birahi serta perhatian berlebihan adalah terlarang. Ada sebuah hadîts yan menyebutkan: “Siapa yang memakai 84 M. Quraish Shihab, Jilbab … op.cit., hlm. 167. 85 Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur’ân, op.cit., hlm. 548. 59 pakaian (yang bertujuan mengundang) popularitas, maka Allah akan mengenakan untuknya pakaian kehinaan pada hari kemudian, lalu dikobarkan pada pakainnya itu api”. (H.R. Abû Daud).86 Yang dimaksud di sini adalah bila tujuan memakainya mengundang perhatian dari laki-laki dan bertujuan memperoleh popularitas. Pemilihan mode busana tertentu juga tercakup di sini, akan tetapi bukan berarti seseorang dilarang memakai pakaian yang indah dan bersih, karena itu itulah justru yang dianjurkan.87 Ketiga, tidak boleh memakai pakaian yang transparan atau ketat. Maksudnya, pakain yang masih menampakkan kulit, atau pakaian ketat yang masih memperlihatkan lekuk-lekuk badan. Sebab, model pakaian semacam itu, pasti akan mengundang perhatian dan rangsangan. Ada sebuah hadîts yang menyebutkan: “Dua kelompok dari penghuni nereka yang merupakan umatku, belum saya lihat keduanya. Wanita-wanita yang berbusana (tetapi) telanjang serta berlenggak-lenggok dan melanggaklenggokkan (orang lain) di atas kepala mereka (sesuatu) seperti punukpunuk unta. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak juga menghirup aromanya. Dan (yang kedua adalah) laki-laki yang memiliki cemeti-cemti seperti seekor sapi. Dengannya mereka menyiksa hamba-hamba Allah”. (H.R. Muslim).88 Berbusana tetapi telanjang, dapat dipahami sebagai memakai pakaian tembus pandang, atau memakai pakaian yang demikian 86 Abû Daud, op.cit., Juz III, hlm. 64. 87 M. Quraish Shihab, Jilbab … op.cit., hlm. 168. 88 Muslim Ibn Hajaj, op.cit., Juz I, hlm. 102. 60 ketat, sehingga nampak dengan jelas lekuk-lekuk badannya. Sedang berlenggak-lenggok dan melenggak-lenggokkan dalam arti gerak-geriknya berlenggak-lenggok antara lain dengan menari atau dalam arti jiwanya mirik tidak lurus atau dan memiringkan pula hati atau melenggaklenggokan pula badan orang lain. Adapun yang diamaksud punuk-punuk unta itu adalah sanggul-sanggul mereka yang dibuat sedemikian rupa sehingga menonjol ke atas bagaikan punuk unta.89 Keempat, tidak boleh memakai pakaian yang meyerupai pakaian laki-laki. Nabi s.a.w. telah bersabda: “Allah mengutuk lelaki yang memakai pakaian perempuan dan mengutuk perempuan yang memakai pakaian lelaki”. (H.R. al-Hakim melalui Abû Hurairah).90 Yang perlu diperhatikan, bahwa peranan adat kebiasaan dan niat sangat menentukan. Karena, boleh jadi ada model pakaian yang dalam suatu masyarakat dinilai sebagai pakaian pria sedang dalam masyarakat lain ia menyerupai pakaian wanita. Seperti halnya model pakaian Jallabiyah di Mesir dan Arab Saudi Arabia yang digunakan oleh pria dan wanita, sedang model pakaian ini mirip dengan long dress yang dipakai wanita di bagian dunia lain. Bisa jadi juga satu model pakaian tadinya dinilai sebagai menyerupai pakaian laki-laki, lalu karena perkembangan masa, ia menjadi pakaian perempuan. Ketiak yang memakainya tidak disentuh oleh ancaman ini, lebih-lebih jika tujuan pemakaiannya bukan untuk meniru lawan jenisnya.91 89 M. Quraish Shihab, Jilbab … op.cit., hlm. 170. 90 Al-Turmudzî, op.cit., Juz I, hlm. 70. 91 M. Quraish Shihab, Jilbab … op.cit., hlm. 171. 61 2. Fungsi Busana sebagai Perhiasan Perhiasan merupakan sesuatu yang dipakai untuk memperelok (memperindah). Tentunya pemakaiannya sendiri harus lebih dahulu menganggap bahwa perhiasan92 tersebut indah, kendati orang lain tidak menilai indah atau pada hakikatnya memang tidak indah. Al-Qur’ân tidak menjelaskan apalagi merinci apa yang disebut perhiasan, atau sesuatu yang “elok”. Sebagian pakar menjelaskan bahwa sesuatu yang elok adalah yang menghasilkan kebebasan dan keserasian. Bentuk tubuh yang elok adalah yang ramping, karena kegemukan membatasi kebebasan bergerak. Sentuhan yang indah adalah sentuhan yang memberi kebebasan memegang sehingga tidak ada duri atau kekasaran yang mengganggu tangan. Suara yang elok adalah suara yang keluar dari tenggorokan tanpa paksaan atau dihadang oleh serak dan 92 Berbicara tentang perhiasan, salah satu yang diperselisihkan para ulama adalah emas dan sutera sebagai pakaian laki-laki. Dalam al-Qur’ân persoalan ini tidak disinggung, tetapi sekian banyak hadîts Nabi s.a.w. menegaskan bahwa keduanya haram dipakai oleh kaum lelaki. Misalnya hadîts: “Ali bin Abi Thalib berkata: “saya melihat Rasûlullâh s.a.w. mengambil sutera lalu beliau meletakkan di sebelah kanannya dan emas diletakkan di sebelah kirinya, kemudian Nabi bersabda: “Kedua hal ini haram bagi lelaki umatku”. (H.R. Abû Dawud dan Nasa’I). Pendapat ulama berbeda-beda tentang diharamkannya kedua hal tersebut bagi kaum lelaki. Antara lain bahwa keduanya menjadi simbol kemewahan dan perhiasan yang berlebihan, sehingga menimbulkan ketidakwajaran kecuali bagi kaum wanita. Selain itu ia dapat mengundang sikap angkuh, atau karena menyerupai pakaian pakaian kaum musyrik. Menurut Muhammad bin Asyur, seorang ulama besar kontemporer serta mufti Tunisia yang telah diakui otoritasnya oleh dunia Islam; menulis dalam bukunya Maqashid al-Syari’ah al-Islamiyah, bahwa ucapakan dan sikap Rasûlullâh s.a.w. tidak selalu harus dipahami sebagai ketetapan hukum. Ada dua belas macam tujuan ucapan dan sikap Rasûlullâh walaupun diakuinya bahwa yang terpenting dan terbanyak adalah dalam bidang syari’at hukum. Salah satu dari kedua belas tujuan tersebut adalah al-hadyu wa al-irsyad (tuntunan dan petunjuk). Menurutnya, boleh jadi Nabi Muhammad s.a.w. memerintah atau melarang, tetapi tujuannya bukan harus melaksanakan itu, melainkan tujuannya adalah tuntunan ke jalan-jalan yang baik. Lihat Muhammad bin Asyur, Maqashid al-Syri’ah al-Islamiyah, Kairo: Dâr al-Katib, 1967, hlm. 32. 62 semacamnya. Ide yang indah adalah ide yang tidak dipaksa atau dihambat oleh ketidaktahuan, takhayul, dan semacamnya. Sedangkan pakaian yang elok adalah yang memberi kebebasan kepada pemakaianya untuk bergerak. 93 Kebebasan haruslah disertai tanggung jawab, karena keindahan harus menghasilkan kebebasan yang bertanggung jawab. Tentu saja pendapat tersebut dapat diterima atau ditolak sekalipun keindahan merupakan dambaan manusia. Namun harus diingat pula bahwa keindahan sangat relatif, tergantung dari sudut pandang masing-masing penilai. Hakikat ini merupakan salah satu sebab mengapa al-Qur’ân tidak menjelaskan secara rinci apa yang dinilainya indah atau elok.94 Wahyu kedua yang dinilai oleh ulama sebagai ayat-ayat yang mengandung informasi pengangkatan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai Rasul antara lain menuntunnya agar menjaga dan terus-menerus meningkatkan kebersihan pakaiannya (Q.S. al-Mudatsir (74): 4).95 Memang salah satu unsur multak keindahan adalah kerbersihan. Itulah sebabnya mengapa Nabi Muhammad S.a.w. senang memakai pakaian putih, bukan saja karena warna ini lebih sesuai dengan iklim Jazirah Arab yang panas, melainkan juga karena warna putih segera menampakkan 93 Lihat M. Quraish Shihab, Wawasan … op.cit., hlm. 166. 94 Ibid., hlm. 167. 95 Lihat Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur’ân, op.cit., hlm. 988. 63 kotoran, sehinga pemakaiannya akan segera terdorong untuk mengenakan pakaian lain yang bersih.96 Al-Qur’ân setelah memerintahkan agar memakai busana yang indah ketika berkunjung ke masjid, mengecam mereka yang mengharamkan perhiasan yang telah diciptakan Allah S.W.T. untuk manusia. Firman-Nya: ... ج ِﻟ ِﻌﺒَﺎ ِد ِﻩ َ ﺧ َﺮ ْ ﺣ ﱠﺮ َم زِﻳ َﻨ َﺔ اﻟﱠﻠ ِﻪ اﱠﻟﺘِﻲ َأ َ ﻦ ْ ﻞ َﻣ ْ ُﻗ Artinya : “Katakanlah!” Siapakah yang mengharamkan perhiasan yang telah Allah keluarkan untuk hamba-hamba-Nya …” (Q.S. al-A’raf (7): 32).97 Karena berhias merupakan naluri manusi, maka ada sebuah hadîts yang mengisahkan seorang sahabat bertanya dalam kasus ini. “Seseorang yang senang pakaiannya indah dan alas kakinya indah (Apakah termasuk keangkuhan?) Nabi menjawab: “Sesunggunya Allah indah, senang kepada keindahan, keangkuhan adalah menolak kebenaran dan menghina orang lain” (H.R. Turmudzî).98 Terdapat sekian hadîts yang menginformasikan bahwa Rasûlullâh s.a.w. menganjurkan agar kuku pun harus dipelihara, dan diperindah. Isteri Nabi s.a.w. Aisyah, meriwayatkan sebuah hadîts bahwa: “Seseorang 96 M. Quraish Shihab, op.cit., hlm. 168. 97 Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur’ân, op.cit., hlm. 225. 98 Al-Turmudzî, op.cit., Juz I, hlm. 89. 64 wanita menyodorkan dengan tangannya sepucuk surat kepada Nabi dari belakang tirai, Nabi berhenti sejenak sebelum menerimanya, dan bersabda: “Saya tidak tahu, apakah yang (menyodorkan surat) ini tangan lelaki atau perempuan. Aisyah berkata: “tangan perempuan”. Nabi kemudian berkata kepada wanita itu: “Seandainya Anda wanita, niscaya Anda akan memelihara kuku Anda (mewarnainya dengan pacar) (H.R. Bukhari).”99 Demikian Nabi menganjurkan agar wanita berhias. Al-Qur’ân memang tidak merinci jenis-jenis perhiasan, apalagi bahan pakaian yang baik digunakan. Perlu diperhatikan, bahwa salah satu yang harus dihindari dalam berhias adalah timbulnya rangsangan birahi dari yang melihatnya (kecuali suami isteri) dan atau sikap tidak sopan dari siapapun. Hal-hal tersebut dapat muncul dari cara berpakaian, berhias, berjalan, berucap, dan sebagainya.100 Berhias tidak dilarang oleh ajaran Islam, karena ia adalah naluri manusiawi. Yang dilarang adalah tabarruj al-hailiyah, salah satu istilah yang digunakan al-Qur’ân (surat al-Ahzâb (33): 33)101 mencakup segala macam cara yang dapat menimbulkan rangsangan birahi kepada selain suami isteri. Termasuk dalam cakupan maksud kata tabarruj menggunakan wang-wangian yang baunya menusuk hidung. Dalam sebuah hadîts Rasûlullâh s.a.w. bersabda: “Wanita yang memapakai 99 Muhammad bin Ismail al-Bukhâri, op.cit., Juz I, hlm. 79. 100 Muhammad Shahrur, op.cit., hlm. 515. 101 Lihat Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur’ân, op.cit., hlm. 672. 65 farfum (yang merangsang) dan lewat di satu majelis (kelompok pria), maka sesungguhnya dia “begini” (yakni bezina)”. (H.R. al-Turmudzî).102 Al-Qur’ân mempersilahkan perempuan berjalan di hadapan lelaki, tetapi diingatkannya agar cara berjalannya jangan sampai mengundang perhatian. Al-Qur’ân juga tidak melarang seseorang berbicara dengan lawan jenisnya, tetapi jangan sampai sikap dan isi pembicaraan mengundang rangsangan dan godaan. 3. Fungsi Perlindungan atau Ketakwaan Telah disebutkan bahwa pakaian tebal dapat melindungi seseorang dari sengatan dingin, dan pakaian yang tipis dari sengatan panas. Hal ini bukanlah hal yang perlu dibuktika, karena yang demikian ini adalah perlindungan secara fisik. Di sisi lain, pakaian memberi pengaruh psikologis bagi pemakainya. Itu sebabnya sekian banyak negara mengubah pakaian militernya, setelah mengalami kekalahan militer. Bahkan Kamal Ataturk di Turki, melarang pemakaian tarbusy (sejenis penutup kepala bagi pria), dan memerintahkan untuk menggantinya dengan topi ala Barat, karena tarbusy dianggapnya mempengaruhi sikap bangsanya serta merupakan lambangan keterbelakangan.103 Pengaruh psikologis dari pakaian dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya jika pergi ke pesta, apabila mengenakan pakaian buruk, atau tidak sesuai dengan situasi, maka pemakainya akan 102 Al-Turmudzî, op.cit., Juz I, hlm. 85. 103 Lihat M. Quraish Shihab, Wawasan … op.cit., hlm. 169. 66 merasa rikuh, atau bahkan kehilangan kepercayaan diri, sebaliknya pun demikian. Kaum sufi, sengaja memakai shuf (kain wol) yang kasar agar dapat menghasikan pengaruh positif dalam jiwa mereka.104 Harus diakui bahwa memang pakaian tidak menciptakan muslimah, tetapi dia dapat mendorong pemakainya untuk berperilaku sebagai muslimah yang baik, atau sebaliknya, tergantung dari cara dan model pakaiannya. Pakaian terhormat, mengundang seseorang untuk berperilaku serta mendatangi tempat-tempat terhormat, sekaligus mencegahnya ke tempat-tempat yang tidak senonoh. Ini salah satu yang dimaksud al-Qur’ân dengan memerintahkan wanita-wanita memakai jilbab.105 Fungsi perlindungan bagi pakaian dapat juga diangkat untuk pakaian ruhani. Libats al-taqwa. Setiap orang dituntut untuk merajut sendiri pakaian ini. Benang atau serat-seratnya adalah tobat, sabar, syukur, qana’ah, ridha, dan sebagainya. Sebuah hadîts menyebutkan: “Iman itu telanjang, pakaiannya adalah takwa” (H.R. Muslim).106 4. Fungsi Penunjuk Identitas Identitas/kepribadian sesuatu adalah yang menggambarkan eksistensinya sekaligus membedakannya dari yang lain. Eksistensi atau keberadaan seseorang ada yang bersifat material dan ada juga yang 104 Ibid., hlm. 170. 105 Ibid., hlm. 171. 106 Muslim Ibn Hajaj, op.cit., Juz I, hlm. 65. 67 imateral. Hal-hal yang bersifat material antara lain tergambar dalam pakaian yang dikenakannya, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’ân: ... ﻦ َ ﻦ َﻓﻠَﺎ ُﻳ ْﺆ َذ ْﻳ َ ن ُﻳ ْﻌ َﺮ ْﻓ ْ ﻚ َأ ْدﻧَﻰ َأ َ َذِﻟ... Artinya : “… Yang demikian itu lebih mudah bagi mereka untuk dikenal …”. (Q.S. al-Ahzâb (33): 59).107 Dapat dibedakan antara murid SD, SMP atau SMA. Bisa juga dibedakan antara Tentara Angkatan Laut, Angkatan Darat, Kopral atau Jenderal dengan melihat apa yang dipakainya. Tidak dapat disangkal bahwa pakaian antara lain berfungsi menunjukkan identitas serta membedakan seseorang dari lainnya. Bahkan tidak jarang ia membedakan status sosial seseorang. Rasûlullâh s.a.w. sendiri sangat menekankan pentingnya identitas muslim, antara lain melalui busana. Karenanya, Rasûlullâh s.a.w. melarang laki-laki yang yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki (H.R. Abû Dawud).108 Kepribadian umat juga harus ada. Ketika Rasûlullâh s.a.w. membicarakan bagaimana cara yang paling tepat untuk menyampaikan/mengundang kaum muslimin melaksanakan shalat, maka ada di antara sahabatnya yang mengusulkan menancapkan tanda sehingga yang melihatnya segera 107 Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur’ân, op.cit., hlm. 678. 108 Lihat Abû Dawud, op.cit., Juz III, hlm. 52. 68 datang. Beliau tidak setuju. Ada lagi yang mengusulkan untuk menggunakan terompet, dan komentar Nabi: “Itu cara Yahudi”. Ada juga yang mengusulkan membunyikan lonceng. Nabi berkata: “Itu cara Nasrani”. Sabda Nabi selanjutnya. Akhirnya yang disetujui Nabi adalah adzan yang deperti yang dikenal sekarang setelah Abdullah bin Zaid alAnshari dan Umar bin Khatab bermimpi tentang cara tersebut. Demikian diriwayatkan oleh Abû Dawud. Yang penting untuk digarisbawahi adalah bahwa Rasul menekankan pentingnya menampilkan kepribadian tersendiri, yang berbeda dengan yang lain. Dari sini dapat dimengerti dari sabdanya: “Barang siapa meniru suatu kaum, maka ia termasuk kelompok kaum itu” (H.R. Bukhari).109 Mengenai kepribadian ruhani (immateri) bahkan ditekankan oleh al-Qur’ân melalui surat al-Hadid (57): 16 yang berbunyi: ﻖ َوﻟَﺎ ﺤﱢ َ ﻦ ا ْﻟ َ ل ِﻣ َ ﺸ َﻊ ُﻗﻠُﻮ ُﺑ ُﻬ ْﻢ ِﻟ ِﺬ ْآ ِﺮ اﻟﱠﻠ ِﻪ َوﻣَﺎ َﻧ َﺰ َﺨ ْ ن َﺗ ْ ﻦ ءَا َﻣﻨُﻮا َأ َ ن ِﻟﱠﻠﺬِﻳ ِ َأَﻟ ْﻢ َﻳ ْﺄ ﺖ ُﻗﻠُﻮ ُﺑ ُﻬ ْﻢ َو َآﺜِﻴ ٌﺮ ْ ﺴ َ ﻋَﻠ ْﻴ ِﻬ ُﻢ ا ْﻟَﺄ َﻣ ُﺪ َﻓ َﻘ َ ل َ ﻞ َﻓﻄَﺎ ُ ﻦ َﻗ ْﺒ ْ ب ِﻣ َ ﻦ أُوﺗُﻮا ا ْﻟ ِﻜﺘَﺎ َ َﻳﻜُﻮﻧُﻮا آَﺎﱠﻟﺬِﻳ ن َ ﺳﻘُﻮ ِ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ ﻓَﺎ Artinya : “Belumlah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun, dan janganlah mereka seperti orang-orang sebelumnya yang telah diberikan al-Kitab (orang Yahudi dan Nasrani). Berlalulah masa yang panjang bagi 109 mereka sehingga hati mereka Lihat Muhammad bin Ismail al-Bukhâri, op.cit., Juz I, hlm. 80. 69 menjadi keras. Kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang fasik”. (Q.S. al-Hadid (57): 16).110 Seorang muslim diharapkan mengenakan pakaian ruhani dan jasmani yang menggambarkan identitasnya.111 Disadari sepenuhnya bahwa Islam tidak datang menentukan mode pakaian tertentu, sehingga setiap masyarakat dan periode, bisa saja menentukan mode yang sesuai dengan seleranya. Namun demikian, agaknya tidak berlebihan jika diharapkan agar dalam berpakaian tercermin identitas itu.112 Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa ditnjau dari fungsinya, maka busana memiliki empat fungsi, yaitu fungsi busana sebagai sebagai penutup aurat, fungsi busana sebagai perhiasan, fungsi busana sebagai perlindungan dan ketakwaan, dan fungsi busana sebagai identitas. Terkait fungsi busana sebagai penutup aurat, maka ada patokanpatokan yang harus diperhatikan dalam berbusana. F. Kontroversi Jilbab Di atas digambaran bahwa salah satu fungsi pakaian adalah sebagai penunjuk identitas, dan dapat pula sebagai penutup aurat. Karenanya, maka tidak diragukan lagi bahwa jilbab bagi seorang wanita merupakan gambaran identitas seorang muslimah, di samping sebagai penutup aurat, yaitu rambut dan leher wanita. Namun persoalan jilbab ini kemudian terjadi debatable mengingat batasan aurat wanita yang harus ditutupi beragam pendapat. Jilbab bisa difungsikan sebagai penutup aurat yaitu rambut dan leher yang menganggap bahwa keduanya merupakan aurat wanita yang harus ditutupi. 110 Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur’ân, op.cit., hlm. 902. 111 Lihat M. Quraish Shihab, Wawasan … op.cit., hlm. 171. 112 M. Quraish Shihab, Jilbab … op.cit., hlm. 67. 70 Sebaliknya, hannya sebagai penampakkan identitas muslihmah saja bagi yang menganggap bahwa rambut dan leher wanita bukan aurat, karenanya tidak harus ditutupi dengan jilbab. Bahkan jilbab juga bisa hanya sebatas asesoris (pelengkap), dan dipakai pada moment-moment tertentu seperti waktu shalat, pengajian, berkAbûng dan menghadiri pernikahan, bahkan dipakai musiman sebagaimana yang dilakukan oleh para artis ketika bulan Ramadhan. Wacana publik tentang jilbab seringkali berputar-putar pada pertanyaan: Apakah ia sebuah ekspresi kultural Arab ataukah substansi ajaran agama; Apakah ia sebuah simbol kesalehan dan ketaatan seseorang terhadap otoritas agama ataukah simbol perlawanan dan pengukuhan identitas seseorang? Banyak feminis “beraliran” Barat memandangnya sebagai sebuah bias kultur patriarkhi serta tanda keterbelakangan, subordinasi dan penindasan terhadap perempuan. Fatima Mernissi, misalnya, menggugat bahwa jilbab hanya menjadi penghalang yang menyembunyikan kaum wanita dari ruang publik. Tapi di sisi lain, jilbab dianggap sebagai pembebas dan ruang negosiasi perempuan.113 Menurut penelitian Stern Nabi Muhammad tidak memperkenalkan kebiasaan berjilbab.” Hansen juga berpendapat “pemingitan dan jilbab merupakan fenomena asing bagi masyarakat Arab dan tak diketahui pada masa Nabi.” Asal-usul jilbab dibahas oleh banyak orang pada tahun 1970-an dan 1980-an. Jilbab telah umum diakui keberadaannya di wilayah 113 Fatima Marnisi, Pemberontakan Wanita, terj. Yogyakarta: LKiS, 1996, hlm. 56. Pada titik ini, jilbab sebenarnya masuk pada arena kontestasi—sebuah permainan makna dan tafsir. Relasi-kuasa bermain dan saling tarik antara kalangan agamawan normatif dan feminis liberal; antara atas nama kepentingan norma (tAbû, aurat, kesucian, dan privasi) dan atas nama kebebasan perempuan (ruang gerak, persamaan dll). 71 Mesopotamia/Mediterania.114 Al-Zarkasyi juga telah mengemukakan sebagaimana dikutip Sri Rahayu Arman; bukti bahwa beberapa kota penting di zaman Romawi dan Yunani sudah menggunakan kostum yang menutupi seluruh anggota badan, kecuali satu bola mata untuk melihat.115 Pandangan yang lebih moderat lahir dari seorang penulis Iran, Navabakhsh: “Semula al-Qur’ân sendiri tak menetapkan kapan wanita harus dihijab dari lingkungan laki-laki. Tidak dikenal sebagai suatu fenomena sosial historis pada masa Nabi. Hijab ketika itu lebih sering diasosiasikan dengan gaya hidup kelas atas di kalangan masyarakat petani dan para pendatang, yang merupakan tradisi pra-Islam di Syria dan adat di kalangan orang-orang Yahudi, Kristen, dan Sasania”.116 Kewajiban berjilbab biasanya didasarkan Q.S al-Nûr (24): 31 dan alAhzâb (33): 59).117 Kedua ayat itu melegitimasi kesucian para pemakai jilbab di ruang privat maupun publik. Sayangnya, jarang sekali diungkap konteks sosial dibalik turunnya ayat-ayat tersebut. Bagi para mufasir, kedua ayat itu turun setelah peristiwa fitnah keji terhadap Aisyah. Fitnah perselingkuhan Aisyah ini sangat menghebohkan umat Islam di Madinah. Fitnah keji itu berakhir setelah turun ayat Q.S al-Nûr: 31, khusus untuk membersihkan nama Aisyah.118 114 Fadwa el-Gundi, Veil: Modesty, Privacy dan Resistance, terj. Mujiburohman “Jilbab: Antara Kesalehan, Kesopanan dan Penawanan”, Jakarta: Serambi, 2003, hlm. 79-89. 115 Lihat Sri Rahayu Arman, “Jilbab; Antara Kesucian dan Resistensi”, dalam Http://www.Islamlib.com. Tgl. 19 Januari 2003. 116 Ibid. 117 Lihat Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur’ân, loc.cit. 118 Lihat Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur’ân, loc.cit. 72 Sejak peristiwa itu turun ayat lain yang cenderung membatasi ruang gerak keluarga Nabi, khususnya dalam Q.S al-Nûr dan al-Ahzâb di mana ayatayat jilbab itu ditemukan. Dilihat dari konteks ayat-ayat jilbab, hijab dan kecenderungan pembatasan perempuan, khususnya kepada keluarga Nabi, seolah merupakan refleksi dari suatu situasi khusus yang terjadi di Madinah ketika itu. Riwayat lain mengukuhkan bahwa suasana masyarakat Madinah ketika itu tak tentram, dalam situasi perang berkepanjangan. Apalagi, umat Islam saat itu baru saja mengalami kekalahan dalam perang Uhud, yang membengkakkan populasi janda dan anak yatim. Janda dan anak-yatimperempuan ketika itu sering kali menjadi objek pelecehan seksual dari lakilaki nakal. Hanya kaum perempuan bangsawanlah yang terhindar dari pelecehan itu karena mereka mengunakan jilbab. Maka, seruan untuk berjilbab pada saat itu adalah salah satu srategi budaya atau tindakan preventif atas terjadinya pelecehan terhadap perempuan.119 Jilbab juga menjadi simbol identitas, status, kelas dan kekuasaan pada konteks kekinian. Menurut Crawley, misalnya, pakaian adalah ekspresi yang paling khas dalam bentuk material dari berbagai tingkatan kehidupan sosial sehingga jilbab menjadi sebuah eksistensi sosial, dan individu dalam komunitasnya. Di Afrika Utara, jilbab menjadi pembungkam perempuan dalam wilayah publik secara umum. Namun, kadangkala juga kerap digunakan oleh perempuan pedesaan bepergian di luar wilayah mereka. Di Yaman, jilbab sebagai simbol status yang terstratifikasi. Bagi perempuan bangsawan memakai syarsyaf, jenis jilbab yang terbuat dari sutera. Sementara perempuan dari status ekonomi yang lebih rendah cenderung memakai sitara.120 Menurut Makhlouf sebagainya dikutip Sri Rahayu Arman menyatakan bahwa “jilbab, walaupun jelas-jelas merupakan pembatasan komunikasi … [dia juga merupakan sebuah simbol] alat komunikasi … [dan] berjilbab tentunya menciptakan suatu perintang bagi ekspresi bebas wanita sebagai seorang pribadi … [tapi jilbab juga meningkatkan] ekspresi diri dan femininitas”.121 Lebih dari itu, jilbab juga menjadi simbol pembebasan dan resistensi. Sebagai gerakan resistensi, ia tak hanya berhenti pada masyarakat Timur 119 Sri Rahayu Arman, loc.cit. 120 Lihat Fadwa al-Gundi, op.cit., hlm. 117. 121 Sri Rahayu Arman, loc.cit. 73 Tengah, melainkan terejawantah dalam masyarakat muslim modern di berbagai belahan dunia. Resistensi adalah sebuah perlawanan atau strategi untuk mengukuhkan eksistensi seseorang atau suatu komunitas.122 Di Aljazair, misalnya, jilbab mempunyai peran penting dalam proses kemerdekaan negara ini. Kolonial Perancis tidak hanya mengontrol hukum Islam—perkara-perkara pidana tapi juga menghancurkan kebudayaan mereka— memberangus adat setempat, dan melarang warga mempelajari bahasa mereka sendiri. Para pendatang Perancis mendominasi wilayah Aljazair dan memegang posisiposisi fungsionaris publik, dan mengontrol pos-pos subordinat di bawahnya. Strategi lainnya adalah mem-Perancis-kan wanita Aljazair dengan mencAbût akar budayanya. Jilbab menjadi target kolonial untuk mengontrol dan melepaskan—untuk mempengaruhi wanita Aljazair agar melepaskan jilbabnya dengan alasan untuk memodernisir Aljazair. Namun, budaya tradisional Arab–Aljazair memandang keluarga adalah pusat di mana dunia sosial moral itu berada; wanita adalah pusat identitas sakral keluarga dan penjaga harga diri dan reputasi keluarga Arab. Keibuan dipandang sakral. Maka, menyerang wanita Muslim, berarti mendestabilisasikan inti sistem sosial-spiritual dan memperkosa secara literal maupun figuratif akar budaya mereka. Dan salah satu bentuk perlawanan Aljazair terhadap apa yang 122 Cudjoe dan Harlow mendefinisikan resistensi sebagai sebuah tindakan yang dirancang untuk membebaskan masyarakat dari penindasnya, dan ia sepenuhnya memasukkan pengalaman hidup dibawah penindasan itu, yang kemudian menjadi prinsip estetik yang otonom. Ibid. 74 dilakukan oleh Perancis itu adalah memperkuat jilbab sebagai bagian dari simbol nasional dan kultural perjuangan wanita Aljazair.123 Di Indonesia, jilbab tidak hanya dipakai orang tua, tapi juga para remaja, pekerja di kantor, instansi maupun pemerintahan, para artis, bahkan para pelacur sekalipun. Tentu, ia pun sarat makna. Di satu sisi, jilbab menjadi simbol pakaian muslimah santri, terutama yang berasal dari pesantren. Di sisi lain, ia dijadikan busana yang lazim dikenakan hanya pada momen-momen kerohanian—shalat, pengajian, berkAbûng, bahkan saat menghadiri pesta pernikahan; sebaliknya tak dipakai pada berbagai aktivitas kesehariannya. Akhir 1980-an ribuan mahasiswi dan pelajar berjilbab membanjiri jalanan di berbagai kota besar. Mereka memprotes kebijakan Mendikbud yang melarang jilbab di sekolah-sekolah umum. Mereka ingin mengukuhkan identitas kemuslimahannya dengan mentradisikan berjilbab. Jilbab lebih dari sekadar kewajiban, tapi simbol kultural yang membedakan komunitas mereka (santri) dengan komunitas lainnya (abangan dan non-muslim).124 Kalangan selebritis sibuk menutupi kepalanya yang biasa terbuka itu dengan jilbab di bulan Ramadhan. Jelas pemakaian jilbab tak ada hubungan dengan kesalehan maupun ketaatan beragama. Sebab, begitu bulan suci itu usai, jilbabnya pun dilepas. Bagi mereka, berjilbab hanyalah tuntutan pasar; strategi untuk meraup keuntungan material dengan penampakan spiritual. Begitu pula para pelacur. Di Nangroe Aceh Darussalam, mereka menyembunyikan identitasnya dengan memakai jilbab. Mengingat posisinya sebagai pekerja seks dalam ruang sosial dianggap hina, kotor, dan melecehkan moralitas, mereka harus mencari simbol sebagai alibi stereotip itu. Dengan memakai jilbab, mereka ingin eksistensi dan identitas mereka diakui dan 123 Fadwa al-Gundi, op.cit., hlm. 233. 124 Sri Rahayu Arman, loc.cit. 75 dihormati di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, tidaklah layak jika kita menggeneralisir bahwa perempuan berjilbab itu berarti suci, sopan, dan saleh. Begitu pula sebalikya, perempuan tidak berjilbab dicitrakan sebagai perempuan kotor, kurang sopan, dan tidak taat beragama.125 Dari paparan di atas dapat ditegaskan lagi bahwa jilbab sebagai salah satu busana yang biasa dipakai seorang muslimah, masih terjadi pro-kontra terkait dengan fungsi jilbab sendiri; apakah sebagai penutup aurat rambut dan leher, sebagai asesoris atau sebagai penampakan identitas. Hal ini terkait dengan batasan aurat perempuan sendiri yang masih terus diperdebatan. 125 Ibid. 76 BAB III ETIKA BERBUSANA MAHASISWI IAIN WALISONGO SEMARANG A. Dinamika dan Ragam Corak Pemikiran Keagamaan Mahasiswa IAIN Walisongo Mahasiswa IAIN Walisongo, tidak jauh berbeda dengan mahasiswa pada umumnya yang dilekati berbagai label, seperti sebagai insan akademik, kaum intelektual, dan calon cendikiawan. Apalagi IAIN Walisongo sendiri sebagai perguruan tinggi berlabel Islam yang tentu saja sebagai konsekuensi logis, label-label Islam pun dilekatkan pula pada mahasiswanya. Secara makro, mahasiswa sering diidentikan sebagai kelompok sosial strategis. Kepadanya dilekatkan berbagai atribut sosial seperti agen perubahan sosial (agent of social change), agen kontrol sosial (agent of social control) dan agen demokrasi (agent of democratization). Atribut-atribut semacam ini sesungguhnya merefleksikan harapan sekaligus tanggung jawab yang harus diemban oleh mahasiswa. Ada kepercayaan di tengah masyarakat bahwa karena kondisinya yang relatif masih terjaga dari vested interest politik, maka mahasiswa menjadi sandaran bagi proses-proses perubahan sosial politik dan demokratisasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Posisinya sebagai cendekiawan muda menjadikan mahasiswa berada dalam kendali idealisme untuk mewujudkan keinginan akan perubahan-perubahan dan pecarian bentuk-bentuk ideal dari kehidupan sosial politik dan kebudayaan. 77 Lewis Coser menggambarkan mahasiswa sebagai komunitas yang kelihatannya tidak pernah puas menerima kenyataan sebagaimana adanya. Mereka mempertanyakan kebenaran yang berlaku pada suatu saat, dalam hubungannya dengan kebenaran yang lebih tinggi dan lebih luas. Menurut Edwar Shils, kaum cendikiawan merupakan orang-orang yang mencari “kebenaran”. Sementara Julien Benda dalam bahasanya mengenai pengkhianatan cendikiawan abad ke-20, menyebutkan bahwa cendikiawan idealnya orang-orang yang bukan mengejar tujuan-tujuan praktis. Cendikiawan merupakan orang-orang yang mencari kepuasan dalam bidang iptek, budaya, teka-teki metafisika. Singkatnya dalam hal-hal yang tidak menghasilkan keuntungan kebendaan. Sedangkan Manheim mengemukakan pandangan yang serupa terutama ketika mengatakan bahwa cendikiawan sebagai suatu kelompok semacam lapisan yang terapung bebas dalam masyarakat, tanpa pertalian dengan suatu kelas tertentu.126 Pandangan-pandangan idealistik tentang mahasiswa sebagai cendikiawan tersebut meletakkan mahasiswa sebagai komunitas yang seolah berada di luar jangkauan pengaruh lingkungan sosial politik. Karena watak kecendikiawanannya mahasiswa dianggap kebal (imune) dari pergulatan sosial politik lingkungan sosialnya.127 126 Komaruddin Hidayat dan Hendro Presetyo, Problem dan Prospek IAIN, Antologi Pendidikan Tinggi Islam, Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam-Dirjen Bimbaga Islam DRPAG RI, 2000, hlm. 14-20. 127 Lihat Fuad Jabali dan Jamhari, IAIN dan Pembaruan Islam di Indonesia, Jakarta: Logos, 2002, hlm. 32. 78 Berbeda dengan itu, bahwa mahasiswa sebenarnya juga bisa dilihat sebagaimana komunitas sosial lainnya. Intelektualisme dan perilaku yang diekspresikannya merupakan produk dari lingkungan sejarah sosial politik tertentu. Dengan demikian peran-peran intelektual dan politik yang dimainkannya juga berhubungan erat dengan pribadi, tokoh, maupun aliran tertentu yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Apalagi jika dilihat dari kenyataan bahwa kampus merupakan lingkungan strategis bagi proses kaderisasi pemimpin masa depan. Karenanya, setiap kelompok sosial dan politik di manapun pasti sangat berkepentingan untuk menjadikan kampus sebagai salah satu basis kekuatan dan dukungan politik.128 Berangkat dari idealitas di atas, pasang surut dinamika intelektual dan sosial politik kampus berjalan seiring dengan dinamika sosial politik bangsa secara umum. Hubungan kampus dan realitas politik juga yang telah mendorong munculnya organisasi-organisasi kemahasiswaan. Dorongan untuk berkiprah dalam percaturan kebangsaan, serta kepentingan partai-partai politik untuk melakukan persemaian kader terdidik telah mendorong berdirinya ormas-ormas kemahasiswaan. Ada Himpinan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Persekutuan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim 128 Fachry Ali, “Kontiuitas dan Pencerahan: Catatan Sejarah Sosial Budaya Alumi IAIN” dalam Komaruddin Hidayat dan Hendro Prasetyo (ed.), Problem dan Prospek IAIN, Antologi Pendidikan Tinggi Islam, Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam-Dirjen Bimbaga Islam DRPAG RI, 2000, hlm. iv. 79 Indonesia (KAMMI) dengan polarisasi dan ideologi masing-masing sehinga menampakkan karakteristik dan nalar akademis serta gerakannya. Dinamika mahasiswa IAIN Walisongo sendiri tidak lepas adanya kecenderungan-kecendrungan umum yang diwarnai dengan polarisasi ideologi, nalar akademik, nalar keagamaan serta pilihan aksi, yang mencerminkan kompleksitas mahasiswa. Sekalipun pada umumnya mahasiswa IAIN Walisongo secara sosiologis berasal dari masyarakat pesantren yang hidup di kawasan pedesaan, akan tetapi melalui interaksi yang simultan merubah nalar mereka secara fantastik, apalagi yang terlibat dalam gerakan-gerakan mahasiswa. Sehingga tidak heran, jika organisasi-organisasi kemahasiswaan seperti HMI, PMII, IMM dan KAMMI juga berkembang subur di IAIN. Sebagai lembaga akademik yang menekankan obyektifitas kritisisme, secara internal IAIN Walisongo sebagaimana IAIN pada umumnya telah memperkenalkan aneka ragam kecendrungan pemikiran dan gerakan keislaman. Proses-proses sosialisasi mahasiswa IAIN dengan berbagai kecenderungan pemikiran keagamaan maupun gerakan keislaman itu telah ikut serta membentuk pluralitas pemikiran keagamaan, ideologi dan gerakan mahasiswa IAIN Walisongo di pentas publik.129 Untuk memupuk nalar kritisisme dan memperkaya khazahan pemikiran, selain berkembangnya oerganisasi-organisasi kemahasiswaan ekstra, seperti HMI, PMII, IMM dan KAMMI, di internal kampus IAIN 129 Lihat Musahadi, dkk., IAIN Walisongo; Mengeja Tradisi Merajut Masa Depan, Semarang: Puslit IAIN Walisongo Bekerja Sama dengan CV. Putakindo Pratama, 2003, hlm. 200. 80 Walisongo berdiri lembaga-lembaga kajian yang dibentuk sebagai unit kegiatan kemahasiswaan di berbagai fakultas, seperti LPO Fakultas Tarbiyah, Lembaga Studi Paradigma Fakultas Dakwah, Forum Sajian Ilmiah Fakultas Syari’ah dan LSAF Fakultas Ushûluddin, di samping ada Kelompok Studi Mahasiswa Walisongo (KSMW) di tingkat Institut. Kemudian penerbitan mahasiswa seperti Edukasi (LPM Fakultas Tarbiyah), IDEA (LPM Fakultas Ushûluddin), MISSI (LPM Fakultas Dakwah) dan Justisia (LPM Fakultas Syari’ah), juga SKM Amanat. Ataupun lembaga pengembangan bakat seni seperti UKM Teater, Music, Mawapala, dll.130 Semuanya menambahkan khazanah dan kecenderungan pemikiran mahasiswa. Sebab, gejala yang tampaknya apolitis itu pada proses selanjutnya justru menjadi medium proses penyadaran sekaligus wadah bagi pembentukan creatif minority mahasiswa IAIN Walisongo. Melalui lembaga kajian dan penerbitan inilah mahasiswa berkumpul dan mendiskusikan persoalanpersoalan teoritik maupun isu-isu sosial politik. Hasil yang tampak dari proses tersebut antara lain pada tata peraturan bagi sivitas akademika khususnya mahasiswa, merupakan hasil rumusan di kalangan mahasiswa sendiri. Misalnya, Tri Etika Kampus IAIN Walisongo Semarang yang terdiri atas etika diniyah, etika ilmiah dan etika ukhwah yang rumusannya ditetapkan melalui SK Rektro No. 13 tahun 1994 merupakan hasil diskusi di KSMW. Rumusan tersebut pada tahun 1999 dijabarkan lagi 130 Ibid., hlm. 2001. 81 sebagai tata tertib mahasiswa dan ditetapkan melalui SK Rektor No. 4 tahun 1999 yang sebagian tim perumusnya adalah mahasiswa.131 Proses pematangan ideologi intelektual tersebut juga membuahkan maraknya lembaga-lembaga studi mahasiswa dan penerbitan-penerbitan mahasiswa di luar unit kegiatan mahasiswa yang resmi di IAIN Walisongo. Banyak lembaga swadaya mahasiswa dibentuk yang tidak langsung sebagai lembaga kajian oleh mahasiswa sendiri. Misalnya LIPPI, FPPI, Formasal, ISC (Islamic Studie Center), HUMANIKA, KM-IAIN, Kosma IAIN, dan CDIS. Pematangan intelektual melalui lembaga-lembaga kajian, atau organisasi-organisasi pergerakan ikut mengarahkan pola kecenderungan pemikiran keagamaan mahasiswa IAIN Walisongo yang beragam. Misalnya, mahasiswa yang ikut lembaga kajian tertentu atau organisasi ekstra tertentu akan memiliki kecenderungan nalar intelektual keagamaan tersendiri. Begitu pula sebaliknya, mahasiswa yang tidak terlibat aktif pada salah satu lembaga kajian atau organisasi ekstra, akan memiliki pola pemikiran yang berbeda. Pola pemikiran keagamaan tersebut sedikit banyak akan terefleksi pada aktivitas keberagamaan mereka. Pemikiran keagamaan132 (relligious thinking) sendiri, merupakan suatu bentuk berpikir yang khas, setidaknya dari segi pendekatan yang digunakannya. Kekhasannya terletak pada adanya pengaruh kepercayaan dan doktrin agama dalam proses mengenali dan memahami suatu obyek. Karenanya, pemikiran keagamaan 131 Ibid., hlm. 2002. 132 Istilah pemikiran keagamaan dapat diartikan sebagai pengungkapan atau ekspresi intelektual orang-orang beragama dalam memandang dunia, baik yang konkrit maupun abstrak, yang berkaitan dengan semua aspek kehidupan manusia. Lihat Djamhjari, Agama dalam Perspektif Sosiologis, Bandung: Alfabeta, 1993, hlm. 34. 82 berkaitan dengan sifat berpikir yang dilandasi penalaran yang khas sebagai seorang pemeluk agama.133 Secara prosedural, pemikiran keagamaan tidak berbeda dari teknik berpikir lainnya. Hanya saja dibatasi dan dibimbing oleh nilainilai dan norma agama. Karenanya, pemikiran keagamaan tetap menggunakan rasio sebagai alat berpikir untuk melakukan analisa, sintesa, evaluasi dan generalisasi.134 Lebih dari itu, menurut pendekatan psikologi, terdapat suatu keunikan dalam pemikiran keagamaan, yaitu kemampuan memadukan hal-hal yang menurut logika bertentangan. Apa yang dipandang kontradiktif oleh rasio terkadang dapat diterima secara bersamaan jika menggunakan corak berpikir keagamaan. Sehingga Robert W. Crapps memandang bahwa idealnya pemikiran keagamaan tersusun dengan koherensi, konsitensi dan kejelasan yang sempurna, walaupun harapan itu terlalu idealistis dan utopian. Sebaliknya, sistem konseptual orang kerap mencakup gagasangagasan yang menurut logika saling berlawanan.135 Ragam pemikiran keagamaan cenderung berjalan bersama atau mengikuti kondisi sosial yang selalu berubah. Karenanya, pemikiran keagamaan merupakan fenomena sosial yang bersifat dinamis, dan berkembang mengikuti gerakan dan dinamika masyarakat dan mengikuti perkembangan yang terjadi di sekitarnya. Sebab, tidak ada paham, persepsi dan pemikiran yang senantiasa terus bertahan dalam proses regenerasi. Secara gradual di dalamnya pasti terjadi pergeseran-pergeseran, baik dalam sistem makna ataupun dalam pemikirannya.136 Bertolak dari asumsi di atas, maka seseorang atau kelompok masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan akan memiliki corak pemikiran keagamaan yang berbeda dengan seseorang atau kelompok masyarakat yang tinggal atau berasal dari pedesaan. Mahasiswa IAIN Walisongo merupakan kelompok masyarakat yang mayoritas tinggal di wilayah perkotaan, atau pinggiran perkotaan (Semarang) yang pada kenyataannya lebih dekat dengan sumber informasi, kehidupan sosialnya heterogen dan lebih dinamis. Seseorang atau kelompok yang mengikuti dan terlibat dalam satu organisasi atau komunitas tertentu, akan memiliki corak pemikiran keagamaan yang berbeda satu sama lain yang pada tahap selanjutnya, hasil pemikiran tersebut diaktualisasikan dengan pilihan 133 Ibid., hlm. 40. 134 Lihat Mukti Ali, Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini, Jakarta: Rajawali Press, 1988, hlm. 102. 135 Lihat Robert W. Crapps (Ed.), An Introduction to Psycology of Religion, terj. Agus M. Hardjana “ Perkembangan Kepribadian dan Keagamaan, Yogyakarta: Kanisius, 1994, hlm. 40. 136 Lihat Dhavamony, Phenomenology of Religion, terj. Sudiarja, dkk., Yogyakarta: Kanisius, 1995, hlm. 23-28. 83 perilakunya. Begitu pula mahasiswa IAIN Walisongo yang terlibat dan aktif pada organisasi kemahasiswaan tertentu dengan polarisasi idiologi gerakan tertentu, akan memiliki corak pemikiran keagamaan yang berbeda pula, dan pada tahapan selanjutnya perbedaan itu bisa diplikasikan dengan aktivitas keagamaan kesehariannya, misalnya tata-cara shalat, ataupun ritual lainnya. Tidak dapat diragukan, bahwa mahasiwa yang aktif atau bergabung dengan HMI, atau IMM, akan memiliki corak pemikiran keagamaan yang lebih modernis137 dan dalam beribadah pun mengikuti pola yang ditradisikan kaum modernis tersebut, karena HMI memang memiliki akar sejarah kedekatan dengan partai-partai Islam seperti Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia). Minimal HMI memiliki kepentingan idiologis sebagai elemen gerakan pembaharuan Islam. Begitu juga IMM yang secara struktural maupun emosional merupakan bagian dari Ormas Islam, yaitu Muhammadiyah. Mahasiwa yang bergabung dengan PMII akan memiliki corak pemikiran keagamaan yang tradisionalis138 (walaupun para aktifisnya 137 Yaitu corak pemikiran keagamaan yang hanya mengakui sifat rasional-ilmiah dan menolak cara pandang mistis yang tidak berdasarkan nalar praktis. Menurut kelompok ini, tradisi masa lalu sudah tidak relevan dengan tuntutan zaman sehingga ia harus dibuang dan ditinggalkan. Karakter utama gerakannya adalah keharusan berpikir kritis dalam soal-soal kemasyarakatan dan keagamaan, penolakan terhadap sikap jumud (kebekuan berpikir) dan taqlid. Turâs dalam pandangan kelompok ini adalah suatu bentuk tradisi yang harus dilampaui. Masyarakat Islam tidak akan maju selama cara berpikir dan orientasi mereka masih ke masa lalu. Karena itu, ia menolak pendekatan yang dilakukan kaum tradisionalis dan juga sekuler. Menurutnya, kaum tradisional telah bersalah dengan menempatkan tradisi pada posisi yang sakral dan salih li kulli zaman wa makan. Padahal kenyataannya, masa kini jelas berbeda dengan masa lalu. Sementara itu, kaum sekuler bersalah telah berlaku eklektis dengan memilih unsur-unsur tertentu dari Barat. Tradisionalis ingin menjadikan masa lalu sebagai model kemajuan. Kelompok sekular, ingin menjadikan orang lain (Barat) sebagai model kemajuan dirinya. Keduanya sama-sama ahistoris, tidak kreatif dan tidak akan berhasil membangun perdaban Islam. Lebih lanjut, kelompok ini menganjurkan untuk menganalisis tradisi-tradisi Islam (termasuk sunnah Rasul s.a.w.) lewat kajian historis. Tradisi-tradisi termasuk sunnah Rasul yang tidak bisa dibuktikan otentisitasnya lewat analisis historis berarti dusta dan harus ditolak. Lihat Abdullah Arwi, al-‘Arab wa al-Fikr al-Tarikhi, Beirut: Markaz Tsaqafi al-Arabi, 1973, hlm. 77-79. 138 Yaitu corak pemikiran keagamaan yang memegang pemikiran ulama Islam masa lalu dan berusaha untuk berpegang teguh pada tradisi yang telah mapan. Bagi kelompok ini, seluruh persoalan umat telah dibicarakan secara tuntas oleh para ulama pendahulu, sehingga sekarang hanya menyatakan kembali apa yang pernah dikerjakan mereka, atau paling banter menganalogikan pada pendapat-pendapatnya. Secara umum mereka menganggap bahwa pintu ijtihad telah ditutup. Ajaran Islam harus diikuti melalui madzhab yang telah ada. Pemikiran tokohtokoh seperti al-Syafi’î dan al-Ghazâlî, yang hidup abad pertengahan, dianggap telah menyelesaikan berbagai persoalan umat sampai akhir zaman. Sedemikian, sehingga pada gilirannya, orang yang mendalami dan menguasai tradisi ikut mendapat berkah, dianggap sebagai tokoh yang harus dijadikan panutan dan mampu untuk menyelesaikan segala persoalan duniawi maupun ukhrawi. Menurut Hassan Hanafi, kecenderungan tradisionalisme pada saatnya melahirkan konsekuensi-konsekuensi tertentu seperti; (1) Eksklusifisme. Karena adanya penokohan, bahkan pensakralan individu, sikap tradisionalistik menggiring terbentuknya sikapsikap ekslufisme yang hanya menghargai dan mengakui kebenaran kelompoknya sendiri dan menolak keberadaan pihak lain. (2) Subjektifisme. Sebagai akibat lanjut dari ekslusifisme, kelompok ini menjadi kehilangan sikap objektif dalam menilai sebuah persoalan. Benar dan salah tidak lagi didasarkan atas persoalannya, tetapi lebih pada asalnya, dan dari/oleh kelompok mana 84 sering mengidentifikasi dengan post-tradisionalis139) karena PMII merupakan kepanjangan tangan dari Nahdlatul Ulama (NU), Ormas Islam yang sangat ketat dalam hal pemeliharaan terhadap tradisi yang telah mapan dan nilai lokal. Sedangkan yang bergabung dengan KAMMI akan memiliki corak keagamaan puritan atau cenderung fundamentalis140, bahkan mereka berafiliasi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sangat getol memperjuangkan syari’at dan moralitas Islam. Sistem pendidikan di IAIN Walisongo juga mempengaruhi dalam membentuk pemikiran keagamaan mahasiswa. Sistem pendidikan IAIN yang khas Islam jelas memiliki spesifikasi tersendiri dan memberi pengaruh yang atau tokoh siapa. (3) Determinisme. Sebagai akibat lebih lanjut dari dua konsekuensi di atas, di mana masyarakat telah tersubordinasi dan terkurung dalam satu warna, mereka menjadi terbiasa menerima “sabda” sang panutan dan menganggapnya sebagai sebuah keniscayaan tanpa ada keinginan untuk mengubah, apalagi menolak. Lihat M. Arkoun, al-Islam al-Akhlaq wa al-Siyasah, Beirut: Markaz al-Inma’ al-Qaumi, 1990, hlm. 171. Lihat pula Hasan Hanafi, al-Turâs wa alTajdid Mauqifuna min al-Turâs al-Qadim, Beirut: Al-Mu’assasah al-Jami’ah li al-Dirasat wa alNasyr wa al-Tauzi, 1992, hlm. 27-29. 139 Yaitu corak pemikiran keagamaan yang berusaha mendekonstruksi warisan-warisan budaya Islam berdasarkan standar-standar modernitas. Kelompok ini, pada satu segi, tidak berbeda dengan kelompok tradisionalistik, yaitu keduanya sama-sama mengakui bahwa warisan tradisi Islam sendiri tetap relevan untuk era modern selama ia dibaca, diintepretasi dan dipahami sesuai standar modernitas. Namun, bagi postradisionalistik, relevansi tradisi Islam tersebut tidak cukup dengan interpretasi baru lewat pendekatan rekonstruktif, tetapi harus lebih dari itu, yakni dekonstruktif. Inilah perbedaan di antara keduanya. Seluruh bangunan pemikiran Islam klasik (turâst), harus dirombak dan dibongkar, setelah sebelumnya diadakan kajian dan analisis terhadapnya. Tujuannya, agar segala yang dianggap absolut berubah menjadi relatif dan yang ahistoris menjadi historis. Mereka berusaha membongkar otoritas teks. Teks suci dan apa yang disebut turâst, tidak lepas dari sejarah, tetapi sebaliknya, justru sepenuhnya terbentuk dan terbakukan dalam sejarah. Karena itu, ia harus dibaca lewat kerangka sejarah, di mana historisisme berarti masa lalu harus dilihat berdasarkan strata historikalnya dan harus dibatasi menurut runtutan kronologis dan fakta-fakta nyata. Dengan metode ini, relevansi antara teks dengan konteks menjadi terhapuskan sehingga yang dibutuhkan adalah makna-makna baru yang secara potensial bersemayam dalam teks. Lihat M. Arkoun Tarikhiyyah al-Fikr al-Arabi al-Islami, Beirut: Markaz al-Inma’ al-Qaumi, 1990, hlm. 14. Lihat pula Mukti Ali, op.cit., hlm. 258. 140 Yaitu pemikiran keagamaan yang sepenuhnya percaya kepada doktrin Islam sebagai satu-satunya alternatif bagi kebangkitan umat manusia. Mereka sangat commited dengan aspek reiligius budaya Islam dengan mengaggap bahwa Islam telah sempurna, mencakup tatanan sosial, politik dan ekonomi sehingga tidak butuh metode maupun teori-teori Barat. Garapan utamanya adalah menghidupkan Islam sebagai agama, budaya sekaligus peradaban, dengan menyerukan kembali kepada sumber asli (al-Qur’ân dan al-sunnah) dan mempraktikkan ajaran Islam sebagaimana yang dicontohkan Rasul dan al-khlafa’ al-rasyidun. Sunnah-sunnah Rasul harus dihidupkan dalam kehidupan modern. Itulah inti dari kebangkitan Islam. Menurut Luthfi Assyaukanie, kecenderungan kelompok ini secara jelas menyatakan perang terhadap ideologi dan pandangan-pandangan asing. Hanya ada dua istilah yang dikenal dalam kamus intelektualnya, (1) Islam (jund Allah dan ashab al-Rasul), (2) Jahiliyah (kuffar dan tagut). Jahiliyah adalah kondisi psikologis yang menolak petunjuk Tuhan. Pada masa lampau, jahiliyah diwakili kaum musyrik Makkah dan Yahudi Madinah. Pada masa modern termanifestasikan pada jahiliyah modern, yakni Barat dan para pemimpin tagut negeri-negeri muslim yang mengadopsi sistem Barat. Lihat Luthfi Assyaukanie, Tipologi dan Wacana Pemikiran Arab Kontemporer, dalam http://www.Islamlibral.com. Tgl. 20 Septmber 2001. 85 cukup kuat dalam pembentukan pemikiran keagamaan. Sistem ataupun lembaga pendidikan keagamaan yang memilih kurikulum dan sistem pengajaran yang menekankan pada pemahaman agama semata secara tekstual, secara teoritis akan melahirkan out put yang memiliki pemahaman dan wawasan berpikir sempit dan cenderung mistis. Sebaliknya, sistem ataupun lembaga pendidikan keagamaan yang di samping memberikan pelajaran agama, juga menekankan pengembangan penalaran, akan melahirkan out put yang memiliki pemikiran yang tidak saja agamis tetapi juga berwawasan luas dan cenderung rasional.141 Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh M. Shadiq Abdullah, bahwa secara umum ada dua kecenderungan yang mewarnai ragam pemikiran keagamaan mahasiswa. Shadiq memetakan pada dua arus besar; kecenderungan autistik (mistis)142 dan kecendrungan realistik (logis).143 Kecenderungan autistik menurut Shadiq, banyak terdapat pada mahasiswa Fakultas Dakwah dan Tarbiyah. Sementara Fakultas Uhsuluddin dan Syari’ah, banyak kecenderungan ke berpikir realistik. Menurut Shadiq, bahwa perbedaan fakultas dengan kurikulm yang berbeda, akan membentuk corak pemikiran keagamaan mahasiswa. Mahasiwa yang banyak menekuni kurikulum yang menekankan pemikiran logis rasional dan filosofis akan mengarahkan dan membentuk pribadi yang cenderung berpikir realistik. Sebaliknya, mahasiswa yang banyak menekuni materi ataupun mata kuliah 141 Menurut Peter McKellar memandang bahwa pemikiran keagamaan dipandang sebagai keadaan yang terus mengalami perubahan, yang bergerak mengikuti garis kontinu mulai dari berpikir autistik sampai ke berpikir realistik. Lihat Djamhari, op.cit., hlm. 47. 142 Yang termasuk dalam corak berpikir autistik adalah mereka yang memiliki pendapat bahwa pernyataan, proposisi, informasi atau pandangan yang bersifat mistis atau fataliitik sebagai suatu yang dapat diterima atau diyakini keabsahannya. 143 Yang termasuk dalam corak berpikir realistik adalah mereka yang memiliki pendapat bahwa pernyataan, proposisi, informasi atau pandangan yang bersifat faktual, real, logis atau rasional sebagai suatu yang dapat diterima atau diyakini kebenarannya. 86 yang kurang menekankan pemikiran kritis, empiris, rasional dan filosofis akan mengarahkan dan membentuk pribadi yang cenderung berpikir autistik.144 Dengan demikian, dapat dipertegas lagi bahwa terdapat keragaman pemikiran keagamaan di kalangan mahasiswa IAIN Walisongo. Keragaman tersebut karena beberapa faktor, seperti pematangan intelektual melalui lembaga-lembaga kajian dan organisasi extra-universiter seperti HMI, PMII, IMM dan KAMMI, di samping karena sistem pendidikan IAIN sendiri. Pada tahapan selanjutnya, perbedaan tersebut mereka aktualisasikan dengan aktivitas rirual mereka. Keragaman pemikiran keagamaan itu juga akan membedakan persepsi dan pola berbusana mahasiswi yang akan penulis bahas lebih lanjut. B. Pemahaman Keagamaan dan Pola Berbusana Mahasiswi IAIN Walisongo Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap etika berbusana mahasiswi IAIN Walisongo, diketahui bahwa para mahasiswi memiliki persepsi yang beragam tentang busana muslimah, se-beragam corak pemahaman keagamaannya. Mereka merfleksikan pemahamannya tentang pola berbusana dengan yang mereka pakai sebagaimana yang penulis amati. 144 Shodiq Abdullah, “Corak Pemikiran Keagamaan Mahasiwa IAIN Walisongo Semarang” dalam Jurnal Penelitian Walisongo, Volume XI, Nomor 2 Nopember, 2003, hlm. 281, dst. Adanya kecenderungan autistik, mengindikasikan bahwa sistem pendidikan yang dikembangkan IAIN Walisongo agaknya belum mampu membentuk dan menciptakan pribadi mahasiswa yang dapat berpikir realistik secara maksimal. Padahal IAIN Wasliongo merupakan lembaga pendidikan tinggi Islam yang diharapkan bukan saja mampu mengembangkan diri sebagai lembaga keagamaan tetapi juga mampu memfungsikan diri sebagai lembaga keilmuan. Sebagai lembaga keilmuan, IAIN dituntut untuk mampu mengembangkan ilmu-ilmu keIslaman dan mampu merespon perkembangan masyarakat terutama dinamika sains dan teknologi modern yang dikembangkan dan bertumpu pada pemikiran empiris dan rasional merupakan ciri berpikir realistik. 87 Secara umum, anggapan yang mengatakan bahwa busana mahasiswi IAIN Walisongo itu kurang modis (kudis) mulai terkikis. Sebab, di Perguruan Tinggi berlabel Islam ini sebagian mahasiswinya sudah bisa tampil keren, seakan-akan tidak mau ketinggalan zaman. Pola berbusana yang dipakai mahasiswi pun terlihat campur aduk (beragam). Ada sebagian mahasiswi yang enjoy memakai busana ketat, ada pula yang berbaju longgar, bahkan ada pula yang memakai jubah. Apakah trend ini juga berpengaruh pada moral mahasiswa, hal ini memerlukan penelitian tersendiri. Beragamanya pola berbusana mahasiswi, beragam pula persepsi tentang pola berbusana yang seharusnya dipakai seorang muslimah. Setelah penulis melakukan observasi, untuk menggali informasi lebih lanjut, penulis melakukan wawancara dengan beberapa mahasiswi. Sebelumnya, penulis mengklasifikasi mereka terutama yang aktif atau bergabung dengan salah satu organisasi kemahasiswaan ekstra seperti HMI, IMM, PMII, dan KAMMI, juga mereka aktif di organisasi intra seperti UKM Music, Teater dan MAWAPALA. Pertimbangannya, karena visi misi organisasi tersebut dapat mengarahkan kecenderungan pemikiran keagamaan yang berbeda, sehingga mengasumsikan pemahaman tentang pola berbusana muslimah yang berbeda pula. Indikatornya, bahwa busana yang dipakai oleh mahasiswi yang bergabung dengan KAMMI berbeda dengan busana yang dipakai mahasiswi yang bergabung dengan HMI, IMM, PMII, apalagi mahasiswi yang aktif di UKM Music, Teater, dan Mawapala. 88 Wawancara penulis dengan beberapa aktivis mahasiswi yang bergabung dengan KAMMI, dapat penulis paparkan; bahwa busana yang seharusnya dipakai oleh mahasiswi IAIN adalah longgar dan dapat menutup aurat rapat-rapat. Seperti yang disampaikan oleh Arista Anggraihani dan Sarah Nur Afni, Tri Yudiasih, Ning Diah K., Da’watul Bararah, Yuli Rahmawati, dan Lia Qatifah. Mereka dan rekan-rekan se-organisasinya memakai busana seperti yang mereka pahami, walaupun tidak aturan yang secara resmi mengenai pola busana yang harus dipakai di organisasinya. Pemandangan busana longgar dan jilbab besar tampak banyak di Fakultas Tarbiyah, karena memang basis KAMII di IAIN Walisongo adalah di Fakultas Tarbiyah.145 Pemahaman yang agak berbeda dari para mahasiswi yang bergabung dengan HMI dan IMM. Mereka menganggap bahwa busana yang cocok untuk mahasiswi IAIN itu tidak harus gombroh, atau longgar, tetapi cukup memakai busana muslimah yang kasual dan sopan. Dengan model kasual, bisa padanan antara celana kulot atau jeans untuk bawahan dan kemeja sebagai atasannya, sebagaimana dikemudkan oleh Ridha Umami, Niklah, Nuriyatul Adlkhiyyah, Neli Afriha, Alfi Rahma Farida, Yuyun Eva Nauli dan Nur Fatimatuz Zahra. Mereka adalah mahasiswi-mahasiswi yang aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).146 Pemahaman yang sama juga disampaikan oleh Erlina 145 Wawancara dilakukan dengan beberapa mahasiswi aktivis KAMMI IAIN Walisongo pada tanggal 5-10 Desember 2004. 146 Wawancara dilakukan dengan beberapa mahasiswi aktivis HMI IAIN Walisongo pada tanggal 11-15 Desember 2004. 89 Rahmawati, Reksa Nila Anityaloka dan Lailatul Maroh. Keduanya bergabung dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).147 Persepsi lain menurut mahasiswi yang kebutulan aktif di Pergerakan Mahasiswi Islam Indonesia (PMII) seperti Samiasih, Siti Maftuhah, Lu’lu’ul Fu’ad, Eny Yuliati, Nurul Aini Khasaningsih, Eva Mushanifah, Ade Herawati, Musharafah, dan Umi Salamah. Mereka memahami bahwa busana muslimah, yang penting menutup aurat, tidak harus gombrong. Memakai busana ketat juga boleh, asal masih kelihatan sopan. Menurut mereka, bahwa orang itu yang penting pribadinya, bukan dilihat dari pakaiannya, meskipun mereka sendiri tidak suka memakai busana ketat dan transparan. Menurut mereka, aturan organisasi yang mereka ikuti tidak mengatur model busana tertentu, atau larangan memakai busana yang ketat/transparan, sehingga rekanrekannya pun ada yang memakai baju ketat.148 Sebaliknya, ada sebagian mahasiswi yang memahami bahwa busana mahasiswi IAIN itu seharusnya yang mengikuti trend mode, supaya tidak dikatakan kurang modis (kudis). Sesuai pemahamannya, mereka pun enjoy memakai model baju yang dikenal dengan istilah “baju adik”. Model busana ini adalah baju ketat (press body), celana ketat, meskipun tetap berjilbab. Di dunia kampus, tren semacam ini bisa dikatakan sebagai model terkini. Di antara mereka yang memahami dan memakai model baju adalah Kisbiyah, Siti 147 Wawancara dilakukan dengan beberapa mahasiswi aktivis IMM IAIN Walisongo pada tanggal 16-18 Desember 2004. 148 Wawancara dilakukan dengan beberapa mahasiswi aktivis PMII IAIN Walisongo pada tanggal 19-24 Desember 2004. 90 Maftuhah, Eva Nur Amalia, Nurul Hidayah, Arina Fatkhatun ‘Arifah, Rifzahara, sebagian mereka adalah adalah aktivis UKM Music dan Teater.149 Model terakhir inilah yang ternyata banyak digemari mahasiswi IAIN Walisongo, tidak hanya mahasiswi yang aktif di UKM Music atau Teaater. Model stelan street dengan padanan celana body cut yang ketat, selalu menjadi fashion idola mereka. Bahkan tidak cukup itu saja, sebagian dari mereka biasanya melengkapi dandanannya dengan goresan make up yang tebal, eyesido, alis yang dikerok, lalu ditebali dengan pensil alis. Belum sempurna, bibir pun lalu dihias dengan lipstik warna-warni, badan disemprot parfum yang aromanya sangat lembut. Dadanan menor-lah yang ditampilkan, dan menampakkan trend ala selibritis. Hasil wawancara dengan Arina misalnya, bahwa dia merasa tidak percaya diri jika tidak memakai “baju adik” (ketat). Dia berprinsip, biarlah mau dibilang ikutan trend, yang jelas enjoy dan gaul.150 Begitu pula menurut Kisbiyah. Menurutnya, sah-sah saja seseorang memakai busana ketat apalagi mengikut trend, kalau hal itu dirasa lebih tepat dan dapat menyesuaikan mode, yang penting masih menutup aurat. Kisbiyah mencotohkan diperbolehkannya mahasiswi memakai celana panjang ketika naik kendaraan; “pakaian celana itu lebih efektif, karena kalau pakai rok akan lebih kelihatan”.151 149 Wawancara dilakukan pada tanggal 24-28 Nopember 2004, setelah sebelumnya mengadakan observasi yang cukup lama. 150 Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Nopember 2004. 151 Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Nopember 2004. 91 Sedangkan Nurul Hidayah, pemakai baju ketat lainnya, juga mengungkapkan alasan yang sama. Dengan jujur mengatakan enjoy-nya memakai baju ketat. Menurutnya, pakaian itu tergantung pada pribadinya masing-masing. Selain enyoy, kebiasaannya memakai baju ketat ini dikarenakan faktor cuaca. Menurutnya, karena di Semarang cuacanya panas, kalau pakai baju yang ombrong malah sumuk (cepat keluar keringat).152 Eny Yulianti juga mengungkapkan bahwa kebiasaan ia memakai baju ketat sudah sejak SMA, selain sebagai pakaian sehari-hari di rumah. Prinsipnya, yang penting memakai jilbab, dan yang penting dalam berbusana, harus mengikuti mode, dan tampil trendi. Sebab, tampil trendi dan mengikuti mode merupakan dambaan setiap perempuan.153 Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa banyak keragaman pemahaman dan pola berbusana di kalangan mahasiswi IAIN Walisongo. Sesuai pemahaman dan pola berbusana dipakai, mereka pun menanggapi model busana ketat yang ternyata dominan di IAIN Walisongo. Adalah Arista Anggraheni dan Sarah Nur Afni yang mengomentari sinis model busana ketat. Menurutnya, trend busana semacam itu tidak wajar dan sangat disayangkan digemari sebagian mahasiswi IAIN yang notabene mahasiswi perguruan tinggi dengan label Islam, apalagi rata-rata hanya ikut-ikutan trend saja. Jika para pemakai baju ketat beralasan untuk lebih efektif dalam beraktivitas, para aktivis KAMII dan yang kebetulan aktif juga di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini justru mempertanyakan, sebeparapa jauh efektif 152 Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Nopember 2004. 153 Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Nopember 2004. 92 dan manfaat mengikuti mode memakai baju ketat. Mode itu hanya menuruti hawa nafsu belaka. Sudah jelas bahwa menutup aurat itu perintah agama dengan tujuan supaya tidak mengundang syahwat. Jika memakai busana yang lekuk-lekuk tubuhnya kelihatan, itu sama saja masih telanjang. Padahal sudah jelas bahwa banyak ayat al-Qur’ân maupun hadîts yang memerintahkan menutup dan menjaga aurat, termasuk untuk tidak memakai busana yang tidak transparan dan ketat. Mereka juga mencontohkan bahwa organisasinya (KAMMI) walaupun tidak ada aturan mengenai pola busana tertentu, tetapi mengharuskan memakai busana yang longgar karena merupakan perintah agama. Menurut mereka, berbaju longgar tidak sampai mengganggu aktivitas mereka, seperti kuliah, kegiatan organisasi, kegiatan-kegiatan sosial, bahkan demonstrasi sekalipun.154 Persepsi yang agak berbeda dikemukakan oleh Ridha Umami dan Alfi Rahma Farida yang juga aktivis HMI. Kemudian Samiasih dan Lu’lu’ yang aktivis PMII. Menurut mereka, mengikuti mode merupakan suatu yang wajar, karena mode memang boleh diikuti. Menurut Islam sendiri tidak ada larangan yang tegas mengikuti mode, akan tetapi norma-norma Islami harus tetap dipegang. Bagaimana mahasiwi kelihatan modis tetapi tidak mengorbankan ajaran Islam itu sendiri. Kerana budaya juga sebagai cipta, rasa dan karsa, wajib bagi orang Islam selalu membawa misi Islam. Trend ini bersifat populer atau cepat berubah. Di dalam menghadapi modenya, mahasiswi dituntut harus bisa menyesuaikan dengan budaya Indonesia dan 154 Wawancara dilakukan pada tanggal 7 Desember 2004. 93 norma agama. Apabila tidak cermat, bisa-bisa hanya menjadi korban mode itu sendiri.155 Itulah persepsi sebagian mahasiswi IAIN Walisongo tentang pola berbusana yang beragam yang kemudian terefleksikan dengan pola busana yang mereka pakai. Fenomena campur-aduknya model busana yang dipakai, merefleksikan pemahaman dan tolok ukur yang mereka gunakan yang sangat dipengaruhi dengan kultur, komunitas dan aktivitas keseharian mereka. C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pola Berbusana Mahasiswi IAIN Walisongo Ragamnya pola berbusana mahasiswi IAIN Walisongo, tidak lepas dari beberapa faktor yang mendorongnya. Pertama, perbedaan organisasi. Pematangan intelektual melalui organisasi-organisasi pergerakan yang membentuk polarisasi gerakan dan corak pemikiran keagamaan, ikut mempengaruhi pemahaman dan pola berbusana mahasiswi IAIN Walisongo. Mahasiswi yang ikut organisasi KAMMI, karena memiliki kecenderungan nalar intelektual keagamaan yang berbeda dengan yang ikut di PMII, HMI, IMM, apalagi yang ikut UKM Music atau Teater, ataupun mahasiswa yang hanya menghabiskan kesehariaannya untuk kuliah oriented dan di kost saja, jelas berbeda pula persepsinya tentang busana muslimah.156 Kedua, pemahaman keagamaan. Mahasiswi yang yang berbusana gombrong kebanyakan yang bergabung dengan KAMMI. Mereka memang 155 Wawancara dilakukan pada tanggal 12 Desember dengan beberapa aktivis HMI IAIN dan aktivis PMII IAIN pada tanggal 20 Desember 2004. 156 Bisa dilihat dari beberapa selebaran, famlet atau buku panduan dan rujukan ataupun AD/ART organisasi masing-masing. 94 dikenal sebagai kelompok yang intens menyuarakan tentang perlunya penerapan nilai-nilai keislaman, termasuk di Kampus IAIN Walisongo. Di dalam berbusana pun mereka berpegang teguh pada ajaran Islam bahwa menutup aurat rapat-rapat, tidak memakai busana transparan atau ketat merupakan perintah dalam al-Qur’ân maupun hadîts. Di samping itu, sebagai tuntutan moral Islam, yang akan membawa pemakainya akan lebih hati-hati terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang agama.157 Begitu juga pemahaman mahasiswi yang ikut HMI, IMM ataupun PMII. Mereka umumnya lebih longgar dalam memahami ajaran Islam dan menekankan bagaimana substansi ajaran Islam itu bisa hidup di kampus IAIN Walisongo. Di alam berbusana pun yang terpenting memenuhi standar kesopanan dan menutup aurat dan tidak harus gombrong.158 Sebaliknya, mereka berbusana ketat, kebanyakan tidak begitu memperdulikan apakah itu larangan atau dibolehkan oleh agama, apakah itu sebagai tuntutan moral Islam atau tidak.159 Ketiga, penampakan identitas. Busana muslimah yang longgar, ataupun jilbab, juga sebagai identitas wanita muslimah. Menurut Aristra Anggraihani, bahwa seorang muslimah dianjurkan untuk menampakkan identitas sebagai wanita yang shalihah, salah satunya dengan pola berbusana. Dengan berbusana yang menutup rapat aurat, berjilbab lebar disertai kehati-hatian dalam berperilaku, jelas akan menjadi suri tauladan perempuan. Secara psikologi pun, busana akan 157 Wawancara dengan Arista Anggraihani, pada tanggal 7 Desember 2004. 158 Hasil rumusan wawancara dengan beberapa aktivis HMI pada tanggal 12 Desember, dengan beberapa aktivis IMM pada tanggal 15 Desember dan aktivis PMII pada tanggal 20 Desember 2004. 159 Hasil rumusan wawancara dengan beberapa aktivis UKM Music dan Teater pada tanggal 25 Nopember 2004. 95 mempengaruhi perilaku seseorang. Misalnya, dengan memakai busana yang gombrong dan jilbab lebar, maka akan merasa sangat tidak etis apabila berbincang-bincang yang tidak penting dengan lawan jenisnya yang bukan muhrim, apalagi lagi sampai berpacaran. Itulah sebabnya dalam organisasi KAMMI, tidak memperbolehkan pacaran.160 Begitu pula bagi mahasiswi yang lebih suka berbusana ketat, bagi mereka yang terpenting bagaimana bisa tampil trendi, dan tidak dikatakan ketinggalan zaman.161 Keampat, faktor kebiasaan. Kebiasaan terkait dengan lingkungan seperti kost, latar belakang pendidikan sebelumnya dan keluarga. Mahasiswi yang terbiasa dengan pola berbusana ketat, maka akan merasa kerempotan jika harus beradaptasi dengan berganti model busananya.162 Kebiasaan juga akibat kuatnya patron client yang dipegang mahasiswi. Berbusana tentu saja dipengaruhi oleh teman-teman satu kost, kakak-kakak, ataupun saudarasaudaranya yang lain yang secara otomatis mereka pun akan menirunya. Kelima, faktor budaya konsumerisme. Inilah yang tampaknya merambah mahasiswi termasuk mahasiswi IAIN Walisongo yang berbusana ketat dengan prinsip mengikuti mode.163 Karena budaya konsumerisme banyak mahasiswi IAIN yang tanpa pikir panjang langsung mengikuti mode busana-busana artis. Akibat tindakan asal-asalan dan kurang selektif ini, mereka tidak bisa 160 161 Wawancara dengan Arista Anggraihani, pada tanggal 7 Desember 2004. Wawancara dengan Eni Yulianti pada tanggal 26 Nopember 2004. 162 Wawancara dengan Eni Yulianti pada tanggal 26 Nopember 2004. 163 Wawancara dengan Siti Maftuhah pada tanggal 25 Nopember 2004. 96 mengidentifikasi bentuk tubuhnya, sehingga seringkali busana-busana yang mereka pakai tidak pas. Keenam, tidak adanya sanksi pelanggaran busana di IAIN Walisongo. Memang berbagai aturan mulai dari aturan Institut, maupun Fakultas seperti di Fakultas Dakwah, dengan menempel SK aturan berbusana, dan di Fakultas Sayri’ah dengan menempel ungkapan bijak “Ajiningin Diri Ana Ing Ati, Ajining Raga Ana Ing Busana”. Namun banyak di antara mahasiswi yang jangankan membaca, menengok saja tidak. Termasuk SK Rektor Nomor 04 Tahun 1999 tentang Tata Tertib Mahasiswa IAIN Walisongo yang tidak boleh memakai pakaian transaparan yang memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya.164 Namun karena tidak adanya sanksi aturan itu tidak diperhatikan mahasiswi. Itulah faktor-faktor yang memepengaruhi pemahaman dan pola berbusana mahasiswi IAIN Walisongo, yaitu karena faktor perbedaan organisasi, faktor pemahaman keagamaan, faktor penampakan identitas, faktor kebiasaan, faktor budaya konsumerisme dan faktor tidak adanya sanksi pelanggaran busana di IAIN Walisongo. 164 Lebih jelas tentang aturan busana ini tertera dalam ayat (1) dan (2) pasal 7. Pada ayat (1) disebutkan: selama mengikuti perkuliahan dan memasuki kantor, mahasiswa dilarang memakai sandal dan kaos tidak berkerah. Ayat (2): bagi mahasiswi harus memakai jilbab dan tidak diperbolehkan berpakaian ketat atau transparan. 97 BAB IV ANALISIS ETIKA BERBUSANA MAHASISWI IAIN WALISONGO SEMARANG A. Analisis terhadap Pemahaman Mahasiswi IAIN Walisongo tentang Etika Berbusana dan Implikasinya Busana merupakan salah satu kebutuhan manusia, sampai kapanpun dan di manapun, baik manusia yang berbudaya maju atau masih terbelakang. Kelompok nudis pun yang menganjurkan menanggalkan busana, merasa membutuhkannya, minimal ketika mereka merasakan udara sangat dingin. Masyarakat Tuareg di Gurun Sahara, Afrika Utara, menutupi seluruh tubuh mereka dengan busana, agar terlindungi dari panas matahari dan pasir yang biasa berterbangan di gurun terbuka itu. Masyarakat yang hidup di kutub mengenakan busana tebal yang terbuat dari kulit agar menghangatkan badan mereka.165 Pemakaian busana juga dapat memberikan keindahan. Misalnya, seseorang yang berada di pedalaman Papua, ketika memakai koteka ratusan tahun yang lalu, pastilah merasa ada unsur keindahan yang ditampilkannya. Sebagaimana halnya seorang diplomat sebuah negara yang mengenakan jas dan back tie pada acara-acara khusus. Seorang wanita Afrika yang menusuk bibirnya, wanita India yang melubangi hidungnya, kesemuanya berupaya menampilkan keindahan melalui apa yang dilakukan dan dipakainya. Bahkan seorang yang memiliki aib pada bagian tubuhnya, akan berusaha mengenakan busana tertentu 165 Lihat M. Quraish Shihab, Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2004, hlm. 29. 98 untuk menutupinya. Jika di lengan seseorang ada bekas luka yang menonjol, maka ia pun akan mengenakan baju berlengan panjang untuk menutupinya. Seorang yang merasa kebotakan adalah keburukan, akan tampil menutupinya dengan wig atau kopiah, sedang jika ia menilainya pertanda kecerdasan, maka boleh jadi ia tidak akan berupaya menutupinya. Wanita Indonesia yang perutnya gendut, tidak akan nyaman memakai busana Sari ala India, karena merasa itu tidak indah, atau dapat menonjolkan keburukannya. Sebaliknya, banyak gadis-gadis di seluruh pelosok kota besar berlomba menampakkan perutnya antara lain guna menampilkan apa yang mereka anggap sebagai keindahan.166 Namun demikian, ukuran keindahan itu berubah-ubah. Dahulu gemuk merupakan pertanda kesejahteraan hidup dan digemari oleh banyak perempuan. Kini banyak di antara mereka yang di-eat dan rela menahan diri tidak makan dan tidak minum, serta berolah raga yang melelahkan, agar nampak ramping dan kurus. Demikianlah, ukuran keindahan berubah-ubah serta berbeda-beda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Busana sangat berkaitan dengan budaya dan perkembangan masyarakat. Di Jepang, wanita memakai kimono. Kini tersebar di seluruh dunia busana jas buat pria. Walau jas pada mulanya dipakai oleh buruh pabrik untuk menunjukkan rasa tidak senang kepada bangsawan yang berbusana mewah. Kini terjadi sebaliknya, justru orang-orang kaya dan berkedudukan sosial tinggi yang banyak memakai jas. Dengan demikian, persepsi orang terhadap pola berbusana berubah- 166 Lihat M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’ân, Bandung: Mizan, 1998, hlm. 163-165. 99 rubah dan beragam. Begitu pula pemakaiannya, selalu ada perubahan dan keragaman.167 Begitu pula pemahaman pola berbusana yang berkembang di kalangan mahasiswi IAIN Walisongo, sangat beragam. Mahasiswi yang bergabung dengan KAMMI memiliki persepsi bahwa pola berbusana yang seharusnya dipakai seorang muslimah (termasuk mahasiswi IAIN Walisongo) harus longgar agar dapat menutup aurat secara rapat, karena menutup aurat merupakan perintah agama.168 Kemudian mahasiswi yang bergabung dengan HMI, IMM ataupun PMII memiliki persepsi bahwa pola berbusana mahasiswi tidak harus longgar, yang penting bisa menutup aurat dan terlihat sopan.169 Sebaliknya, mahasiswi yang bergabung dengan UKM Music, Teater dan MAWAPALA kebanyakan memiliki persepsi bahwa busana yang seharusnya dipakai mahasiswi adalah yang trendy, mengikuti mode dan tidak ketinggalan zaman.170 Mereka merefleksikan pemahamannya dengan model busana yang dipakai. Mahasiswi yang bergabung dengan KAMMI mengenakan busana yang gombrong, jilbab besar dan menutup seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan, kakinya pun dibungkus dengan kaos kaki. Mahasiswi yang bergabung dengan HMI, IMM dan PMII juga merefleksikan pemahamannya dengan mengenakan busana yang tidak terlalu longgar, sehingga terkesan biasa-biasa saja. 167 Lihat M. Quraish Shihab, Jilbab … op.cit., hlm. 30. 168 Wawancara dengan Ning Diah K., aktivis KAMMI IAIN Walisongo tanggal 7 Desember 2004. 169 Hasil rumusan wawancara dengan beberapa aktivis HMI, IMM dan PMII, tanggal 11-24 Desember 2004. 170 Wawancara dengan Nurul Hidayah, aktivis UKM Musik, tanggal 26 Nopember 2004. 100 Sebaliknya, mahasiswi yang memahami bahwa pola berbusana yang seharusnya dipakai mahasiswi IAIN harus yang trendy dan mengikuti mode, mereka refleksikan dengan memilih mengenakan busana yang ketat, pras body, sehingga memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya, sebab model demikianlah termasuk model busana terkini. Karenanya, dandanan menorlah yang tampak. Ada sedikit persamaan prinsip mengenai pemahaman fungsional busana yaitu “dapat menutup aurat” antara mahasiswi yang ikut KAMMI dengan yang ikut HMI, IMM dan PMII. Walaupun batasan aurat sendiri masih ada kesamaran, dan mereka pun memahaminya berbeda-beda. Memang, persoalan aurat ini sepanjang sejarahnya selalu debatable, baik di kalangan pemikir Islam klasik maupun kontemporer. Ulama klasik sendiri dalam mendiskusikan batas aurat wanita yang harus ditutupi, secara garis besar dapat dikelompokkan pada dua arus besar. Pertama, kelompok yang menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita tanpa kecuali adalah aurat, sehingga harus ditutup rapat-rapat. Sehingga busana yang harus dipakai seorang muslimah pun harus menutup seluruh aurat tersebut. Kedua, kelompok yang mengecualikan wajah dan telapak tangan. Ada pula yang menambah beberapa pengecualian, seperti kaki sebagaimana yang kemukakan oleh Abû Hanifah. Rujukan dan pertimbangan yang digunakan kelompok pertama banyak pada teks-teks al-Qur’ân dan hadîts. Sedangkan kelompok kedua, di samping teks-teks al-Qur’ân dan hadîts, juga pertimbangan logika dan adat istiadat serta prinsip umum agama.171 171 Lihat misalanya M. Quraish Shihab, Jilbab … op.cit., hlm. 52, dst. 101 Bahan diskusi dalam menentukan batas aurat perempuan baik oleh kelompok pertama maupun kelompok kedua, berangkat dari ayat al-Qur’ân surat al-Ahzâb ayat 33 yang berbunyi: ﻦ ﺟﻠَﺎﺑِﻴ ِﺒ ِﻬ ﱠ َ ﻦ ْ ﻦ ِﻣ ﻋَﻠ ْﻴ ِﻬ ﱠ َ ﻦ َ ﻦ ُﻳ ْﺪﻧِﻴ َ ﻚ َو ِﻧﺴَﺎ ِء ا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨِﻴ َ ﻚ َو َﺑﻨَﺎ ِﺗ َﺟ ِ ﻞ ِﻟَﺄ ْزوَا ْ ﻲ ُﻗ ﻳَﺎَأ ﱡﻳﻬَﺎ اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱡ .ﻏﻔُﻮرًا َرﺣِﻴﻤًﺎ َ ن اﻟﱠﻠ ُﻪ َ ﻦ َوآَﺎ َ ﻦ َﻓﻠَﺎ ُﻳ ْﺆ َذ ْﻳ َ ن ُﻳ ْﻌ َﺮ ْﻓ ْ ﻚ َأ ْدﻧَﻰ َأ َ َذِﻟ Artinya : “Hai Nabi! Katakanlah kepada isteri-isterimu, dan anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita orang-orang mukmin, agar mereka mengeluarkan atas diri merea jilbab mereka. Itu menjadikan mereka lebih mudah dikenal, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. al-Ahzâb (33) : 59).172 Asbâb al-nuzul turunnya ayat tersebut menurut sebagian mufasir bahwa ketika itu cara berbusana wanita merdeka dan budak, wanita baik-baik dan wanita yang kurang sopan hampir sama. Karenanya, lelaki nakal seringkali mengganggunya, khususnya budak-budak itu. Untuk menghindari gangguan tersebut, serta menampakkan keterhormatan wanita muslimah, ayat itu diturunkan.173 Fokus perdabatan dan argumentasinya baik yang digunakan oleh kelompok yang memahami seluruh tubuh wanita aurat, atau kelompok yang mengecualikan telapak tangan dan wajah, terletak pada kalimat “yudnina ‘alaihina min jalabibihina (agar mereka mengeluarkan atas diri merea jilbab mereka)”. Kata jalabib merupakan bentuk jamak dari kata jilbab. Kata ini kemudian diperselisihkan maknanya oleh para ahli bahasa Arab. 172 Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur’ân, al-Qur’ân dan Terjemahnya, Madinah: Mujamma’ al-Malik Fahd li Thiba’at Mushaf al-Syarif, 1418 H., hlm. 678. 173 M. Quraish Shihab, Jilbab … op.cit., hlm. 63. 102 Menurut kelompok yang memahami bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat, memaknai kata jilbab berarti busana yang menutupi baju dan kerudung yang sedang dipakai, sehingga modelnya seperti selimut. Ibn Jarir (w. 923 M.) meriwayatkan bahwa Muhammad Ibn Sirin bertanya kepada ‘Abidah al-Salamani tentang maksud penggalan ayat itu, lalu ‘Abidah mengangkat semacam selendang yang dipakainya dan memakainya sambil menutup seluruh kepalanya hingga menutupi pula kedua alisnya dan menutupi wajahnya dan membuka mata kirinya untuk melihat dari arah sebelah kirinya.174 Sementara al-Baqi (1406-1480 M.) menyebut beberapa pendapat tentang makna jilbab. Antara lain, baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau busana wanita, atau busana yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, atau semua busana yang menutupi badan wanita.175 Menurut kelompok yang mengecualikan telapak tangan dan wajah menyatakan bahwa tidak sepenuhnya benar maksud makna kata tersebut. Jika yang dimaksud dengan jilbab adalah baju, maka ia adalah busana yang menutupi tangan dan kakinya; kalau kerudung maka perintah mengulurkannya adalah menutup wajah dan lehernya. Jika maknanya busana yang menutupi baju, maka perintah mengulurkannya adalalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua badan dan pakain. Selanjutnya, mereka berpendapat bahwa ketentuan itu hanya berlaku pada zaman Nabi s.a.w. di mana ketika itu ada 174 Lihat Mahmud al-Alusi, Ruh al-Ma’ani, Jilid XXII, Cairo: al-Muniriyyah, 1985, hlm. 89. 175 Lihat Ibrahim ibn Umar al-Baqi, Nazhm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar, Jilid V, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1995, hlm. 135. 103 perbudakan dan diperlukan adanya pembeda antara mereka dan wanita-wanita merdeka, serta bertujuan menghindarkan gangguan lelaki nakal. Menurut penganut paham terakhir ini, jika tujuan tersebut telah dapat dicapai dengan satu dan lain cara, maka ketika itu busana yang dikenakan telah sejalan dengan tuntutan agama.176 Adapun hadîts yang dijadikan rujukan oleh kelompok yang memahami bahwa seluruh tubuh wanita sebagai aurat sehingga harus ditutupi rapat-rapat antara lain hadîts yang diriwayatkan oleh al-Turmidzi: “Dari Ibn Mas’ud bahwa Nabi s.a.w. bersabda: “wanita adalah aurat, maka apabila dia keluar (rumah), maka setan tampil membelakakkan matanya dan bermaksud buruk terhadapnya”. (H.R. al-Turmudzî).177 Al-Turmudzî sebagai perawi hadîts menilai bahwa hadîts tersebut berkualitas Hasan dalam arti perawinya memiliki sedikit kelemahan yaitu ingatannya dan gharib, yakni tidak diriwayatkan kecuali melalui seorang demi seorang. Menurut M. Quraish Shihab, bahwa kalaupun kualitas hadîts tersebut dinilai Shahîh, tidaklah menunjukkan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat. Karena kata “wanita adalah aurat”, dapat berarti bagian-bagian tertentu dari badan atau gerakannya yang rawan menimbulkan rangsangan. Hadîts ini juga tidak dapat dijadikan alasan untuk melarang wanita keluar rumah; paling tinggi, dia hanyalah merupakan peringatan agar wanita menutup auratnya dengan baik dan bersikap sopan sesuai dengan tuntutan agama, lebih-lebih 176 Lihat M. Quraish Shihab, Jilbab … op.cit., hlm. 64-65. 177 Al-Turmudzî, Sunan al-Turmudzî, Juz I, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th., hlm. 16. 104 apabila dia keluar rumah, agar tidak merangsang kehadiran dan gangguan setan, baik setan manusia maupun setan jin.178 Hadîts lainnya adalah yang diriwayatkan oleh al-Bukhâri: “Dari Ibn Umar r.a. bahwa Nabi s.a.w. bersabda: “Tidak (dibenarkan) wanita yang sedang berihram memakai cadar (penutup wajah) dan tidak juga memakai kaus tangan’. (H.R. Bukhâri).179 Di samping al-Bukhâri, hadîts tersebut juga diriwayatkan oleh Nasa’i dan Ahmad. Menurut kelompok pertama, hadîts tersebut menunjukkan bahwa ketika itu wanita-wanita muslimah memakai cadar dalam kesehariannya. Argumen ini ditolak oleh kelompok kedua dengan menyatakan bahwa dalam teks hadîts tidak ada yang menunjukkan semua wanita ketika itu bercadar. Ini dapat dibuktikan dengan banyaknya hadîts-hadîts lain yang dapat dijadikan dasar bahwa banyak wanita ketika itu tidak memakai cadar. Kalaupun mereka bercadar, maka itu bisa saja dilakukan bukan atas dasar kewajiban agama, tetapi kehendak mereka sendiri, karena memang tidak ada salahnya wanita bercadar.180 Adapun hadîts-hadîts yang dijadikan rujukan oleh kelompok ulama yang mengecualikan telapak tangan dan wajah di antaranya hadîts yang diriwayatkan oleh Abû Daud: “Aisyah r.a. berkata bahwa Asma putri Abû Bakar r.a. datang menemui Rasûlullâh s.a.w. dengan mengenakan busana tipis 178 Banyak hadîts-hadîts lain yang menunjukkan wanita pada zaman Nabi keluar rumah untuk melakukan kegiatan positif. Lihat M. Quraish Shihab, Jilbab … op.cit., hlm. 87. 179 Muhammad bin Ismail al-Bukhâri, Shahîh Bukhâri, Juz I, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th., hlm. 64. 180 Lihat M. Quraish Shihab, Jilbab … op.cit., hlm. 88-89. 105 (transparan), maka Rasûlullâh s.a.w. berpaing enggan melihatnya dan bersabda: “Hai Asma, sesungguhnya perempuan jika telah haid, tidak lagi wajar terlihat darinya kecuali ini dan ini (sambil beiau menunjuk ke wajah dan kedua telapak tangan beliau” (H.R. Abû Daud).181 Di samping Abû Dawud, hadîts tersebut juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi. Hadîts di atas memiliki rentetan perawi yang menjadi bahasan panjang, serta penerimaan dan penolakan ulama-ulama. Akan tetapi, hadîts itulah yang dijadikan oleh kelompok yang menganggap telapak tangan dan wajah wanita bukan aurat, sehingga tidak harus ditutupi. Misalnya yang dikemukakan oleh Muhammad Nashiruddin al-Albani.182 Begitu juga menurut Abû A’la al-Maududi, yang menyatakan bahwa walaupun hadîts di atas terjadi perdebatan, akan tetapi hadîts tersebut dapat diamalkan. Hanya saja, alMaududi memberikan catatan, bahwa wanita diperbolehkan menampakkan wajah dan telapak tangannya adalah menurut kebiasaan, bahkan bisa saja menampakkan seluruh tangan karena kebutuhan tertentu.183 Hadîts lain yang dijadikan rujukan adalah yang diriwayatkan oleh Bukhâri: Muslim dan Abû Daud: “Rasûlullâh s.a.w. membonceng al-Fadh putra al-‘Abbas pada hari al-Nahr (lebaran haji) di belakang kendaraan (unta) 181 Lihat Abû Dawud, Sunan Abû Dawud, Juz III, Beirut: Dar al-Ihya al-Sunnah alNabawiyah, t.th., Hadîts No. 4104. hlm. 103. 182 Nashiruddin al-Albani, Ilbab al-Mar’ah al-Muslimah fi al-Kitab wa al-Sunnah, Yordania: Al-Maktabah al-Islamiyah, 1413 H., hlm. 44. 183 Lihat Abû A’la al-Maududi, al-Hijab, Beirut: Dâr al-Firk, t.th., hlm. 24, dst. Alasan alMaududi tersebut sebanarnya ditolak oleh al-Albani, karena adanya ketidakjelasan. Atas dasar apa al-Maududi mengklasifikasi bahwa “Ini untuk kebiasaan dan itu untuk kebutuhan”? Mengapa misalnya tidak dikatakan “Yang ini adalah terbaik dan itu dapat ditoleransi”?. Lihat Nashiruddin al-Albani, op.cit., hlm. 46. 106 beliau. Al-Fadh adalah seorang pria yang berseri (gagah). Nabi s.a.w. berdiri memberi fatwa pada khalayak. Lalu datang seorang perempuan dari suku Khats’am, berseri (cantik) dan bertanya kepada Rasûlullâh s.a.w. Al-Fadh (terus-menerus) memandangnya dan kecantikan wanita itu menakjbukannya, maka Nabi menoleh sedang al-Fadh melihat kepadanya (wanita itu), lalu Nabi s.a.w. memalingkan dengan tangan beliau dagu al-Fahdl, maka beliau memalingkan wajah al-Fadh dari pandangan kepada wanita itu. Lalu wanita itu berkata: “sesungguhnya kewajiban yang ditetapkan Allah atas hambahamba-Nya adalah haji (tetapi) saya mendapatkan ayah saya dalam keadaan tua tidak mampu duduk di atas kendaraan, maka apakah boleh saya menghajikan untuknya? Nabi menjawab: “Ya”. (H.R. Bukhâri).184 Di samping al-Bukhâri, hadîts tersebut juga diriwayatkan oleh Abûd Daud, Muslim, dll. Menurut kelompok kedua, hadîts di atas menunjukkan bahwa telapak tangan wanita dan wajah bukanlah aurat, sehingga tidak harus ditutup.185 Di samping itu, masih banyak hadîts-hadîts lain yang dijadikan argumen, baik oleh kelompok yang memahami bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat ataupun kelompok yang mengecualikan telapak tangan dan wajah. Adapuan pandangan ulama kontemporer, walaupun masih banyak yang memegangi pendapat ulama terdahulu, nampaknya sudah cukup beragam. Misalnya pandangan yang disampaikan oleh Qasim Amin (18031908 M.) bahwa tidak ada satu ketetapan agama (nash dari syari’at) yang mewajibkan busana tertentu bagi perempuan, misalnya seperti jilbab 184 Muhammad bin Ismail al-Bukhâri, op.cit., Juz I, hlm. 69. 185 Lihat M. Quraish Shihahb, Jilbab … op.cit., hlm. 96-97. 107 sebagaimana yang dikenal selama ini dalam masyarakat Islam.186 Busana tersebut merupakan adat kebiasaan yang lahir akibat pergaulan masyarakat Islam dengan bangsa-bangsa lain yang mereka anggap baik. Kemudian mereka menirunya dan menilainya sebagai tuntutan agama. Menurutnya, alQur’ân juga membolehkan perempuan menampakkan sebagian dari tubuhnya di hadapan orang-orang yang bukan mahramnya, akan tetapi al-Qur’ân tidak menentukan bagian-bagian dari anggota tubuh itu yang boleh terbuka.187 Gagasan seperti ini mendapat dukungan dari pemikir muslim lainnya seperti Muhammad Abduh (1849-1905 M) dan muridnya, Rasyid Ridha (1865-1935 M.). Bahkan Rasyid Ridha dalam majalah al-Manar menyatakan bahwa gagasan tersebut sebagai salah satu pemikiran terpenting pada masa tersebut.188 Secara garis besar, pandangan ulama kontemporer mengenai busana muslimah juga dapat dikelompokkan pada dua arus besar walaupun tidak terpaut dengan pendapat ulama klasik. Pertama, kelompok yang 186 Qasim Amin menilai tentang cadar, misalnya cadar dipakai oleh kalangan wanita-wanita maju dan kaya serta menengah hingga akhir abad XX di Mesir. Benih perubahan baru terjadi setelah sekian banyak cendekiawan Mesir yang berkunjung dan belajar di Eropa, khususnya Perancis, lalu mereka kembali membawa angin perubahan serta pandangan-pandangan baru yang selama ini belum dikenal oleh negeri-negeri Islam, seperti Mesir. Memang sebelumnya sudah ada sementara perempuan yang menanggalkan busana tertutup akibat bergaulan mereka dengan wanita-wanita Barat, khususnya Perancis yang datang ke Mesir di bawah pimpinan Napoleon (1798-1801 M.), tetapi ketika itu belum ada ajakan sistematis atas nama ajaran Islam. Mereka yang menanggalkan busana tertutup itu adalah perempuan-perempuan yang dinilai kerabat-kerabat atau bahkan yang telah melanggar budaya dan ajaran agama. Ajakan sistematis dan secara terangterangan baru dimulai sekembalinya sekian banyak cendikiawan Mesir setelah selesainya studi mereka di Perancis. Lihat Qasim Amin, Tahrir al-Mar’ah, Mesir: Percetakan Muhammad Zakiy al-Din, 1347 H., hlm. 54-56. 187 Ibid., hlm. 57-58. 188 Lihat Muhammad Fuad al-Barazi, Hijab al-Mar’ah al-Muslimah, Jilid II, Riyadh: Adhwa al-Salaf, 1999, hlm. 473. 108 mengemukakan pendangannya tanpa dalil keagamaan. Kalaupun ada itu sangat lemah dan tidak sejalan dengan kaidah dan disiplin ilmu agama. Seperti pendapat bahwa bahwa busana tertutup (penutup aurat) merupakan salah satu bentuk perbudakan dan lahir ketika laki-laki menguasai dan memperbudak wanita. Ada pula yang menyatakan bahwa busana tertutup seperti jilbab telah menutup keterlibatan perempuan dalam kehidupan politik, agama, akhlak dan lain-lain. Ada pula yang dengan tegas berkata bahwa pada dasarnya wanita berbusana tertutup atau telanjang, keduanya menjadikan wanita sebagai jasad semata. Ketika menutup badan mengandung arti bahwa wanita adalah fitnah (penggoda/perayu) dan wanita akan merayu laki-laki bila membuka busana.189 Pendapat semacam ini sangat subjektif dan tidak disertai dalil sedikitpun. Kalaupun menggunakan dalil, mereka menafsirkannya tidak sejalan dengan kaidah-kaidah bahasa Arab karena kedangkalan pengetahuan agama, tidak dapat memahami konteks ayat, asbâb al-nuzul atau bahkan hanya mengambil sepotong-sepotong ayat atau hadîts dengan mengabaikan lanjutannya. Kedua, pandangan yang merujuk kepada kaidah-kaidah keagamaan yang juga diakui oleh para ulama terdahulu, hanya saja dalam penerapannya tidak sepaham dengan ulama terdahulu. Misalnya pemahaman bahwa perempuan selain boleh tidak menutup wajah dan telapak tangan juga boleh tidak menutup kaki, seperti yang dikemukakan oleh Abû Hanifah. Jika kaki juga harus ditutup, maka akan menimbulkan kesulitan dalam beraktivitas. 189 Lihat Nawal al-Sa’dawi dan Hibah Ra’uf Izzat dalam al-Mar’ah, Wa al-Din wa alAkhlak, Mesir: Dâr al-Fikr al-Mu’ashir, 2000, hlm. 28-30. 109 Pertimbangannya didasarkan pada kaidah fiqh; “ketika sesuatu telah menyempit yakni sulit, maka segera lahir kelapangan, yakni kemudahan (idza dhaqa al-syai’ ittasa’). Oleh karena itu, para cendikiawan kontemporer memperluas bagian-bagian tubuh wanita yang tidak lagi dinilai sebagai aurat antara lain karena lahirnya profesi-profesi baru yang mereka nilai menyulitkan untuk melakukannya jika pelakunya menutup bagian-bagian tubuh dimaksud.190 Karena al-Qur’ân tidak menentukan secara jelas dan rinci batas-batas aurat atau bagian badan yang tidak boleh kelihatan karena rawan rangsangan, maka memunculkan pemahaman yang beragam. Seandainya ada ketentuan yang pasti dan batas yang jelas, dapat dipastikan bahwa kaum muslimin termasuk ulama-ulamanya sejak dahulu hingga kini tidak akan berbeda pemahaman. Secara umum, baik pandangan klasik maupun kontemporer dalam mencoba mencari batas-batas aurat yang harus ditutupi melalui penelahaan terhadap al-Qur’ân, hadîts, maupun pertimbangan logika, adat istiadat, kerawanan rangsangan syahwat, maupun pertimbangan moral/etika. Perbedaan interpretasi pun kerap muncul, karena sudut pandang yang berbeda. Efek panjang dari perbedaan pemahaman terhadap batas aurat yang harus ditutupi tersebut tereflesikan dari beragamnya pola busana muslimah yang ada saat ini, seperti yang terdapat di kalangan mahasiswi IAIN Walisongo. 190 Lihat M. Quraish Shihab, Jilbab … op.cit., hlm. 127-128. 110 Mereka pun memiliki pemahaman tentang pola berbusana yang seharusnya dipakai oleh seorang muslimah dengan perspektif masing-masing. Untuk mengukur, manakah pola berbusana mahasiswi IAIN Walisongo yang sesuai dengan etika Islam, atau sebaliknya mana yang menyimpang, apakah pola berbusana ala KAMMI, ataukah ala HMI, IMM dan PMII, atau sebaliknya pola busana ketat ala mahasiswi UKM Music, Teater dan MWAPALA? Perlu kiranya melihat prinsip-prinsip etika yang dibangun Islam. Etika Islam sendiri merupakan nilai-nilai, norma-norma yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang penekanannya pada suatu tindakan baik buruk, susila-asusila yang bersumber dari wahyu Tuhan, yaitu al-Qur’ân atau hadîts. Artinya, semua tindakan harus mengikuti patokanpatokan tersebut, termasuk pola berbusana. Pilihan seseorang terhadap pola busana, tentunya juga mengejar sesuatu yang baik, karena kebaikan merupakan tanggung jawab moral bagi semua manusia, dan pelaksanaan dari tanggung jawab ini sebagai pencerminan dari jiwa yang beretika. Berarti, dalam berbusana harus bisa memfungsionalkan sifat-sifat manusia untuk mempertahankan nilai-nilai pribadi yang luhur, serta dapat mendudukkan nilai harga diri sebagai manusia yang luhur. Karenanya, pola busana yang sesuai dengan prinsip etika Islam, tentunya yang memenuhi kreteria itu. Dengan prinsip menutup aurat dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh atau transparan yang dapat memancing shahwat yang melihatnya, serta dengan batasan masih kelihat sopan sekiranya 111 pemahaman dan pola berbusana mahasiswi IAIN yang bergabung dengan HMI, IMM dan PMII, masih dalam bingkai etika berbusana yang sesuai dengan etika Islam. Sebab, menurut mereka menurut mereka bahwa dalam berbusana yang terpenting memenuhi standar kesopanan dan menutup aurat. Apalagi pola busana seperti yang dipahami dan dipakai oleh mahasiswi yang tergabung dengan KAMMI, bahwa berbusana haruslah menutup aurat rapat-rapat. Mereka berpegang teguh pada ajaran Islam bahwa menutup aurat rapat-rapat, tidak memakai busana transparan atau ketat merupakan perintah dalam al-Qur’ân maupun hadîts. Di samping itu, sebagai tuntutan moral Islam, yang akan membawa pemakainya akan lebih hati-hati terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang agama. Dengan berbusana yang menutup rapat aurat, berjilbab lebar disertai kehati-hatian dalam berperilaku, jelas akan menjadi suri tauladan perempuan. Secara psikologi busana akan mempengaruhi perilaku seseorang. Misalnya, dengan memakai busana yang gombrong dan jilbab lebar, maka akan merasa sangat tidak etis apabila berbincang-bincang yang tidak penting dengan lawan jenisnya yang bukan muhrim. Sebaliknya, mahasiswi yang memiliki persepsi bahwa pola berbusana mahasiswi IAIN haruslah mengikuti mode, dan mereka lebih suka memilih busana yang ketat, seperti mahasiswi yang aktif di UKM Music, UKM Teater, UKM Mawapala, kebanyakan tidak begitu memperdulikan apakah itu larangan atau dibolehkan oleh agama, apakah itu sebagai tuntutan etika Islam atau tidak. Karenanya, pola berbusana ketat yang mereka pakai yang 112 memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya bertentangan dengan etika Islam, apalagi prinsip mereka hanya mengikut trend mode. Penilaian ini tentunya dengan mengacu patokan-patokan berbusana yang sesuai dengan etika Islam. Patokan-patokan tersebut seperti tidak boleh tabarruj atau menampakkan “perhiasan” dalam pengertian yang umum yang biasanya tidak dinampakkan oleh wanita baik-baik, atau memakai sesuatu yang tidak wajar dipakai, seperti ber-make up secara berlebihan, berlenggaklenggok dan segala macam sikap yang mengundang perhatian laki-laki. Kemudian tidak boleh berbusana yang transparan atau ketat, sebab akan mengundang perhatian dan rangsangan. Selanjutnya tidak boleh memakai busana yang meyerupai busana laki-laki. Dengan demikian, dapat ditegaskan lagi bahwa pemahaman dan pola berbusana mahasiswi yang harus menutup rapat aurat seperti yang dipersepsikan dan dipakai oleh mahasiswi yang tergabung dengan KAMMI, sesuai dengan etika Islam. Begitu juga persepsi dan pola berbusana dengan prinsip menutup aurat, tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh dan tidak transparan seperti yang dipahami dan dipakai oleh mahasiswi yang tergabung dengan HMI, IMM, dan PMII juga sudah sesuai dengan prinsip etika Islam. Sedangkan pemahaman dan pola berbusana ketat, menampakkan lekuk-lekuk tubuh dan transparan sebagaimana yang dipersepsikan dan dipakai oleh mahasiswi yang tergabung dengan UKM Music, UKM Teater dan UKM Mawapala tidak sesuai dengan etika Islam. 113 B. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pola Berbusana Mahasiswi IAIN Walisongo Pada bab terdahulu telah diilustrasikan faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman dan pola berbusana mahasiswi IAIN Walisongo, yaitu karena perbedaan organisasi, pemahaman keagamaan, penampakan identitas, kebiasaa, karena budaya konsumerisme, dan tidak adanya sanksi pelanggaran busana. Pada prinsipnya, faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan pada faktor internal dan eksternal. 1. Faktor Internal Faktor-faktor yang dapat dikelompokkan sebagai faktor internal pemahaman dan pola berbusana mahasiswi IAIN Walisongo seperti perbedaan organisasi dan pemahaman keagamaan. Polarasisasi organisasi kemahasiswan seperti KAMMI, HMII, IMM, PMII maupun yang ikut UKM Music, Teater dan Mawapala, akan membentuk nalar intelektual dan cara pandang dalam menilai suatu persoalan. Perbedaan persepsi itu sangat didukung oleh organisasi-organisasi yang memberikan larangan terhadap pemakaian pola berbusana tertentu, ataupun yang memberikan kebebasan. Karenanya, akan memunculkan pola berbusana ala mahasiswi KAMMI dengan pola busana longgar, jilbab lebar, begitu pula pola berbusana lain yang beragam. Kemudian pemahaman keagamaan. Jika detemukan bahwa mahasiswi yang memakai busana gombrong (longgar) yang menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan kebanyakan mahasiswi yang tergabung dengan KAMMI, sangat dipengaruhi oleh sudut pandang 114 keagamaan. KAMMI memang dikenal organisasi kemahasiswaan yang sangat comite dan intens dalam menyuarakan tentang perlunya penerapan nilai-nilai ke-Islaman, termasuk di Kampus IAIN Walisongo. Mereka memandang, bahwa pola berbusana yang mereka kenakan, dan pola pergaulan yang mereka tekankan, sebagai tuntutan Islam karena didukung oleh sumber al-Qur’ân, hadîts maupun ulama yang punya otoritas di dalamnya. Itulah salah satu perintah agama, bahwa seorang muslimah diwajibkan menutup seluruh auratnya. Dengan menutup aurat rapat-rapat, diharapkan akan membawa seseorang lebih berhati-hati terhadap perilaku yang dilarang agama.191 Begitu pula mahasiswi yang memandang bahwa pola berbusana muslimah tidak harus longgar, yang penting dapat menutup aurat. Mahasiswa dengan type pemahaman seperti ini, umumnya lebih longgar dalam memahami ajaran Islam. Bagi mereka, yang terpenting bagaimana substansi dari ajaran Islam itu. Di dalam berbusana pun yang terpenting memenuhi standar kesopanan dan menutup aurat. Sebab al-Qur’ân sendiri sebagai rujukan utama ajaran Islam, tidak menentukan pola berbusana standar yang harus dipakai muslimah. Batasan aurat sendiri masih belum jelas. Kalaupun ada dalil, itu pun multi-interpretasi.192 Sebaliknya, mahasiswi yang dengan bangganya memahami dan memakai busana ketat, 191 Hasil rumusan wawancara dengan beberapa aktivis KAMMI IAIN Walisongo pada tanggal 5-10 Desember 2004. 192 Hasil rumusan wawancara dengan beberapa aktivis HMI, IMM dan PMII, pada tanggal 11-14, Desember 2004. 115 kebanyakan tidak begitu memperdulikan apakah itu larangan atau dibolehkan oleh agama, apakah itu sebagai tuntutan moral Islam atau tidak, apakah itu menutup aurat atau justru menunjukkan aurat, yang penting pemakainya merasa nyaman.193 Menurut Sarlito Wirawan, secara psikologi mengapa aurat harus ditutupi (tidak boleh ditampakkan), sebenarnya ada dua pihak yang terkena dampaknya, yaitu yang bersangkutan sendiri dan yang melihatnya. Bagi yang bersangkutan menimbulkan rasa malu. Sedangkan yang menyaksikannya bisa timbul seperti terangsang, bangkit shahwatnya, atau risi, malu dan sebagainya. Walaupun perasaan-perasaan yang ditimbulkan ini, subjektif sifatnya, tergantung pada kondisi orang-orang yang bersangkutan dan sistem nilai yang dianutnya.194 Apa yang dikemukakan oleh Sarlito di atas dikemukakan juga oleh sementara cendikiawan, bahkan di antara mereka ada yang merujuk kepada ayat al-Qur’ân untuk mendukungnya. Menurut mereka, al-Qur’ân memberi kelonggaran kepada perempuan untuk menanggalkan “hiasannya” kepada sekian banyak orang yang diduga tidak akan tersangsang apabila ada bagian-bagian tertentu dari wanita itu yang 193 Hasil rumusan wawancara dengan beberapa aktivis UKM Music, Teater dan Mawapala pada tanggal 24-28 Nopember 2004. 194 Sebagai contoh, wanita Jawa yang masih berbusana tradisional, menganggap biasa untuk memperlihatkan dadan bagian atas yang terbuka. Ataupun baju renang, yang dipakai dalam pertandingan renang oleh atlt-atlit putri, pada umumnya tidak menimbulkan masalah apa-apa. Di masyarakat yang masih terbelakang seperti di Bali pada masa lalu, atau di suku-suku Irian Jaya, payudara wanita dibiarkan terbuka saja dan hubungan seks berlangsung tetap sebagaimana yang diatur adat istiadat setempat (justru lebih sopan daripada dalam masyarakat yang lebih beradab). Lihat Sarlito Wirawan, Kajian Islam tentang Berbagai Masalah Kontemporer, Jakarta: Lembaga Penelitian IAIN Syarif Hidayatullah 1988, hlm. 249. 116 terbuka dan terlihat. Mereka yang diduga tidak terangsang seperti orang impotent, orang yang sudah sangat tua, atau pada suatu aktivitas yang memang memaksa untuk melihat aurat seperti untuk pelayanan pengobatan.195 Atas dasar inilah ulama-ulama terdahulu menetapkan adanya perbedaan antara aurat wanita merdeka dan hamba sahaya. Dengan dasar itu pula sementara cendikiawan kontemporer mengembalikan persoalan apa yang dinilai aurat kepada kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat, di mana dapat terjadi perbedaan dalam penilaian tentang bagian-bagian badan yang rawan dan yang tidak rawan, yang menimbulkan rangsangan birahi dan yang tidak menimbulkannya.196 Meskipun demikian, bukan berarti Islam melepaskan kendali kepada adat-kebiasaan, tanpa kontrol dari prinsip-prinsip ajaran agama serta norma-norma etika. Manusia dan masyarakat memiliki potensi negatif yang memungkinkan timbulnya kebiasaan buruk dan tidak sejalan dengan nilai-nilai agama. Bukankah kini sudah menjadi pemandangan sehari-hari banyak terlihat perempuan berbusana yang masih memperlihatkan hampir sekujur paha dan dadanya? Menjadikan adat kebiasaan sebagai dasar pertimbangan dalam menilai sesuatu tanpa kontrol nilai-nilai agama dan dalam koridornya, mengakibatkan runtuhnya nilainilai agama. Sedang salah satu tujuan pokok kehadiran agama adalah 195 196 Lihat M. Quraish Shihab, Jilbab … op.cit., hlm. 134-135. Ibid., hlm. 136. 117 memelihara kelangsungan nilai-nilainya. Karenanya, betapapun longgarnya seorang ulama atau cendikiawan muslim dalam hal aurat, masing-masing mereka tetap menegaskan adanya bagian-bagian tubuh baik pria maupun wanita yang selalu dapat menimbulkan rangsangan sehingga harus tetap tertutup, kendati bagian badan itu telah terbiasa terlihat. 2. Faktor Eksternal Faktor-faktor yang dapat dikelompokkan sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi pemahaman dan pola berbusana mahasiswi IAIN Walisong seperti penampakan identitas. Memang, busana di samping akan menampakkan identitas sesorang yang berbudaya, juga memberi dampak psikologis bagi pemakainya ataupun yang melihatnya. Misalnya pergi ke pesta dengan mengenakan busana sehari-hari, pasti akan merasa rikuh, sebaliknya, akan lebih percaya diri jika memakai busana istimewa. Karena itu, sementara negara mengganti busana militernya dengan warna dan bentuk lain, setelah kekalahan mereka, agar sisa-sisa pengaruh negatif dari kekalahan dapat terkikis. Di Mesir pada masa pemerintahan Muhammad Ali yang berasal dari Turki (1805-1849 M) hinga akhir masa Raja Faruq (Juli 1952 M) kaum pria mengenakan penutup kepala tharbusy yang berasal dari Turki, tetapi begitu terjadi revolusi di bawah pimpinan Nasser, tharbusy ditanggalkan guna menghidupkan rasa nasionalisme dan mengikis habis pengaruh Turki. Dampak psikologi bagi yang melihatnya, 118 bisa dicontohnya misalnya para hakim di beberapa negara memakai wig (rambut palsu penutup kepala) antara lain guna memberi kesan wibawa di hadapan yang hadir di persidangan. Di Indonesia misalnya, ada orang yang sengaja memakai serban agar memberi kesan kesalehan atau ketekunan beragama. Ada juga anak-anak muda yang sengaja merobek jeansnya, atau memakai kalung di lehernya untuk mengesankan-paling tidak di hadapan teman sebayanya-bahwa ia adalah anak muda yang “funky” dan mengikuti trend. Karenanya, busana akan memberi dampak bagi pemakai dan yang melihatnya. Suatu negara juga menetapkan busana-busana tertentu dengan model dan warna tertentu bagi angkatan-angkatan perangnya, untuk membedakannya dengan angkatan perang negara lain, karena busana dapat menjadi pembeda antara seorang bahkan masyarakat dengan yang lain. Bahkan ada lambang-lambang dan tanda-tanda khusus dalam angkatan bersenjata, untuk membedakan status dan pangkat seseorang. Begitulah fungsi busana sebagai pembeda atau pengenal. Agama memperkenalkan pula busana-busana khusus, baik untuk beribadah maupun tidak. Menurut ajaran Islam, ketika melaksnaakan ibdah haji atau umrah ada busana-busana khusus buat pria yakni yang tidak berjahit, sedangkan wanita tidak diperkenankan menutup wajahnya. Di Mesir, ada kelompok dari para biarawan Kristen Ortodoks memakai busana bahkan alas kaki yang berwarna hitam. Mereka membiarkan jenggot dan rambut mereka yang hitam terurai tanpa dicukur. Mereka 119 merasa bahwa dalam busana serta hitam meraka menemukan kedamaian. Warna hitam itu mereka pertahankan hingga mereka masuk ke liang lahad. Agama Budha juga menetapkan busana dan warna tertentu. Di Iran, ayatullah-ayatullah/agamawan ada yang memakai serban putih dan ada juga serban hitam. Itu untuk membedakan keduanya dari segi garis keturunan. Busana muslimah yang longgar, ataupun jilbab seperti yang dipakai mahasiswi KAMMI, menurut mereka juga sebagai identitas wanita muslimah. Seorang muslimah dianjurkan untuk menampakkan identitas sebagai wanita yang shalihah, salah satunya dengan pola berbusana. Dengan berbusana yang menutup rapat aurat, berjilbab lebar disertai kehati-hatian dalam berperilaku, jelas akan menjadi suri tauladan perempuan. Secara psikologi pun, busana akan mempengaruhi perilaku seseorang. Misalnya, dengan memakai busana yang longgar (gombrong) dan jilbab lebar, maka akan merasa sangat tidak etis apabila bercengkrama dengan lawan jenisnya yang bukan muhrim.197 Begitu pula mahasiswi yang berbusana ketat. Mereka dengan percaya diri berusaha mensosialisasikan dirinya sebagai seorang yang dapat terlihat gaul, bisa tampil keren dan tidak ketinggalan zaman.198 197 Hasil rumusan wawancara dengan beberapa aktivis HMI, IMM dan PMII, tanggal 11-24 Desember 2004. 198 Hasil rumusan wawancara dengan beberapa aktivis UKM Music, Teater dan Mawapala pada tanggal 24-28 Nopember 2004. 120 Kemudian karena kebiasaan yang terkait dengan lingkungan, seperti kost, latar belakang pendidikan sebelumnya maupun keluarga. Mahasiswi yang terbiasa dengan pola berbusana ketat gombrong, tentu akan merasa risih jika harus memakai busana ketat. Sebaliknya, mahasiswi yang sudah terbiasa dengan busana ketat, tentu akan merasa kerepotan jika harus beradaptasi dengan berganti model. Kuatnya patron client yang dipegang mahasiswi, juga akan membiasakan mahasiswi akan meniru pola berbusana teman-teman atau seniornya. Selain itu, faktor konsumerisme yang merambah mahasiswi termasuk mahasiswi IAIN Walisongo juga sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi pola berbusana mahasiswi, terutama yang berbusana ketat. Tanpa pikir panjang, mahasiswi langsung mengikuti mode busana-busana artis yang ingin tampil ala selibritis. Sehingga terkadang mereka tidak bisa mengidentifikasi bentuk tubuhnya dengan busana-busana yang mereka pakai. Kemudian karena tidak adanya sanksi pelanggaran busana di IAIN Walisongo. Walaupun telah diatur oleh IAIN tentang pola busana mahasiswa, namun karena tidak adanya sangsi bagi yang melanggar, kecuali teguran dari beberapa dosen, membuat mahasiswa tidak mengindahkan aturan itu. Dengan demikian, dapat ditegaskan lagi bahwa faktor-faktor yang menpengaruhi pemahaman dan pola berbusana mahasiswi IAIN dapat dikelompokkan pada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti pemahaman keagamaan dan perbedaan organisasi. Sedangkan faktor eksternalnya 121 seperti ingin menampakkan identitas, budaya konsumerisme, kebiasaan dan tidak adanya sanksi pelanggaran busana di IAIN. C. Pola Ideal Etika Berbusana Mahasiswi IAIN Walisongo Busana dapat dikatakan sebagai produk budaya, sekaligus tuntutan moral agama. Dari sini lahir apa yang dinamai busana tradisional, daerah dan nasional, juga busana resmi untuk perayaan tertentu, dan apakain tertentu untuk profesi tertentu, serta busana untuk ibadah. Namun perlu dicatat bahwa sebagian dari tuntutan agama pun lahir dari budaya masyarakat, karena agama sangat mempertimbangkan kondisi masyarakat, sehingga mentolelir adatistiadat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Tidak mustahil menurut sementara pakar-bahwa bentuk busana yang ditetapkan atau dianjurkan oleh suatu agama, justru lahir dari budaya yang berkembang ketika itu. Namun yang jelas, moral, cita rasa keindahan, dan sejarah ikut serta menciptakan ikatan-ikatan khusus bagi anggota masyarakat yang antara lain melahirkan bentuk busana dan warna-warni favorit. Memang, unsur keindahan dan moral pada busana tidak dapat dilepaskan, tetapi ada masyarakat yang menekankan pada unsur keindahannya dan menomorduakankalau enggan berkata mengabaikan-sisi moralitasnya dan ada pula sebaliknya. Unsur keindahan sendiri dapat berubah-ubah. Sekadar contoh, kalau dahulu di negara Cina keindahan wanita antara lain dilihat pada kakinya yang kecil, sehingga untuk menampilkannya sejak kecil mereka memakai terompah 122 besi, maka kini hal itu tidak lagi demikian. Dahulu boleh jadi rambut belum lagi dikenal sebagai faktor keindahan, tetapi kini sementara wanita menjadikannya faktor yang sangat penting. Demikian tolok ukur keindahan pun mengalami perubahan dan perkembangan. Di dunia Barat unsur keindahan dinomorsatukan, dan unsur moral seandainya mereka pertimbangkan maka tidak jarang telah mengalami perubahan yang sangat jauh dari tuntutan moral agama. Pengaruh Barat ke dunia Timur tidak sedikit, sehingga ada pula masyarakat Timur yang mengikuti mode busana Barat walau bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya masyarakatnya. Sementara itu ada pula kelompok masyarakat Timur, lebih-lebih yang beragama Islam yang menempuh arah yang sepenuhnya berlawanan dengan arah dunia Barat itu. Mereka mengedepankan unsur moral dan nilai-nilai agama, dan menomorduakan unsur keindahan, bahkan boleh jadi ada di antara mereka yang mengabaikannya sama sekali, baik ditinjau dari segi perkembangan masyarakat menyangkut rasa kecantikan, maupun ditinjau dari izin yang diberikan agama. Jilbab sebagai busana muslimah yang, juga merupakan salah mode busana dari sekian model-model sebagaimana disebutkan di atas. Pemakai jilbab dalam arti busana yang menutup seluruh tubuh wanita atau kecuali wajah dan tangannya yang pernah mengendor dalam banyak masyarakat Islam sejak akhir abad XIX, kembali marak sekitar dua puluh tahun terakhir ini dan kelihatannya dari hari ke hari semakin banyak peminatnya. Persoalan tersebut menjadi semakin marak dan terangkat ke dunia internasional setelah 123 Pemerintah Perancis merencanakan bahkan kini telah menetapkan larangan penggunaan simbol-simbol agama di sekolah-sekolah, dan yang salah satu di antaranya yang mereka nilai sebagai simbol agama adalah jilbab. Pro dan kontra tentang kebijakan itu lahir bukan saja di Perancis, tetapi banyak di belahan dunia. Di Mesir, Pemimpin Tinggi al-Azhar, Sayyid Muhammad Thanthawi dikecam oleh banyak kalangan muslimin akibat pandangannya yang menyatakan bahwa Pemerintah Perancis bebas mengambil kebijakan sesuai dengan apa yang dianggapnya baik, kendati berjilbab adalah kewajiban bagi kaum muslimat. Di sisi lain, yang mengecam Pemerintah Perancis berkaitan dengan kebijakan itu, bukan saja kaum muslimin yang berpendapat bahwa jilbab adalah kewajiban agama, tetapi juga mereka yang tidak menilainya wajib, bahkan dari kalangan non muslim, antara lain dengan alasan bahwa kebijakan itu melanggar Hak-hak Asasi Manusia. Di Indonesia sendiri, gelombang demonstrasi menentang kebijakan itu datang dari organisasi-organisasi yang comite dan intens menyuarakan perlunya penerapan syari’at Islam, seperti Hizb Tahrir Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Front Pembela Islam (FPI) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Banyak analisis tentang faktor-faktor yang mendukung tersebarnya fenomena berjilbab di kalangan kaum muslimat. Tidak dapat disangkal bahwa mengentalnya kesadaran beragama merupakan salah satu faktor utamanya. Namun, agaknya tidak dapat menyatakan bahwa itulah satu-satunya faktor. Karena, diakui atau tidak, ada wanita-wanita yang memakai jilbab tetapi apa 124 yang dipakainya itu, atau gerak-gerik yang diperagakannya, tidak sejalan dengan tuntutan agama dan budaya masyarakat Islam. Di sini jilbab sebagai salah atu mode berbusana yang merambah ke mana-mana. Salah satu faktor yang juga diduga sebagai pendorong maraknya pemakaian jilbab adalah faktor ekonomi. Mahalnya salon-salon kecantikan serta tuntutan gerak cepat dan praktis, menjadikan sementara perempuan memilih jalan pintas dengan mengenakan jilbab. Demikian pandangan sementara para pakar. Bisa jadi juga maraknya berjilbab itu adalah sebagai sikap pertentangan terhadap dunia Barat yang seringkali menggunakan standar ganda sambil melecehkan umat Islam dan agamanya.199 Ada juga yang menduga bahwa pemakaian jilbab adalah simbol pandangan politik yang pada mulanya diwajibkan oleh kelompok-kelompok Islam politik guna membedakan sementara wanita yang berada di bawah panji-panji kelompok-kelompok itu dengan wanita-wanita muslimah yang lain atau yang non muslimah. Lalu kelompok-kelompok itu berpegang teguh dengannya sebagai simbol mereka dan memberinya corak keagamaan, sebagaimana dilakukan oleh sementara pria yang memakai busana longgar dan panjang (ala Mesir atau Saudi Arabiya) atau ala India dan Pakistan dan menduga bahwa itu adalah busana Islami. 199 Memang, sikap demikian bisa lahir dari siapa pun yang tersinggung kehormatannya. Mantan Pemimpin Tertinggi al-Azhar, Syaikh Abdul Halim Mahmud yang merupakan alumni Universitas al-Azhar dan meraih gelar doktor dalam bidang filsafat di Sorbon University, Perancis, pada mulanya mengenakan busana ala Barat. Tetapi, begitu ia mendengar ucapan yang melecehkan al-Azhar dari Jamal Abdu Nasser yang ketika itu adalah Presiden Mesir, Syaikh Abdul Hallim menampakkan kemarahannya dan menanggalkan busana ala Barat sambil mengenakan dan menganjurkan semua civitas Akademika al-Azhar agar memakai busana resmi al-Azhar, yakni jubah dengan penutup kepala berwarna merah putih. Lihat Ra’uf Syalabi, Syeikh al-Islam Abdul Halim Mahmud, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1982, hlm. 633-634. 125 Itulah gambaran makro tentang beragamnya pola busana dan masih sarat akan makna. Begitu juga busana mahasiswi IAIN Walisongo. Lantas kriteria pola berbusana ideal bagi mahasiswi IAIN Walisongo semacam apa? Apakah model busana gombrong dan berjilbab lebar yang menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan tangan, ataukah yang berbusana ketat? Bagaimana pula agar dapat tampil modis, akan tetapi dapat mencerminkan pribadi yang luhur dan sesuai tuntunan syari’at, seperti label yang dilekatkan pada IAIN, yaitu perguruan tinggi dengan basis ke-Islaman? Betapa idealnya jika mahasiswi IAIN Walisongo memakai busana dengan mode tertentu tidak sebatas penampakan identitas, akan tetapi sebagai alat untuk menjaga kehormatan sebagai mahasiswi perguruan tinggal dengan label Islam dengan memperhatikan etika dan estetika. Dengan demikian akan mengesankan pribadi yang mandiri, cerdas, religius, praktis tetapi tetap trendy. Trend apapun yang akan diikuti mahasiswi IAIN, sangatlah bergantung pada diri mahasiswi sendiri. Kecerdasan mereka memilih mode busana adalah langkah tepat, sebelum mereka menjadi tampak rendah moralnya. Inilah kiranya yang perlu diperhatikan oleh mahasiswi IAIN Walisongo, terutama yang lebih suka berbusana ketat dengan ingin tampil keran dan mengikuti mode. Tampaknya, ketegasan aturan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran busana juga perlu diterapkan di IAIN. Karena sebagai institusi pendidikan Islam yang diharapkan mencetak intelektual yang memiliki 126 kapasitas ilmu Islaman, tentunya juga dapat menjunjung tinggi etika, termasuk dalam berbusana. 127 BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Setelah melakukan pembahasan dan analisa secara menyeluruh dalam bab-bab sebelumnya, dengan memperhatikan asumsi-asumsi sebelumnya tentang Etika Religius Berbusana Mahasiswi IAIN Walisongo Semarang, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Pemahaman mahasiswi IAIN Walisongo Semarang terhadap etika berbusana cukup beragam. Mahasiswi yang bergabung dengan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) memahami bahwa pola busana yang dipakai oleh seorang muslimah (termasuk mahasiswi) seharusnya yang longgar sehingga dapat menutup aurat rapat-rapat, tidak boleh transparan/ketat, sebab dengan pola berbusana seperti itu diharapkan membawa pemakainya pada perilaku yang mencerminkan etika Islam. Mahasiswa yang bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) memahami bahwa pola berbusana muslimah yang penting dapat menutup aurat, bentuknya tidak harus longgar, yang penting masih kelihatan sopan. Sebaliknya, mahasiswi yang bergabung dengan UKM Music, Teater dan Mawapala, lebih memahami bahwa busana yang seharusnya dipakai mahasiswi harus mengikuti mode, sehingga mengesankan mahasiswi IAIN tidak ketinggalan zaman dalam berbusana. 2. Implikasi dari pemahaman tersebut mereka ekspresikan dengan pola busana yang mereka kenakan. Karenanya, akan nampak mahasiswi yang 128 bergabung dengan KAMMI dengan pola berbusana yang gombrong (longgar), jilbab besar yang dapat menutup rapat aurat, termasuk membungkus kaki dengan kaos kaki. Pilihan terhadap pola busana yang mereka kenakan didasari dengan pemahaman keagamaan yang sangat ketat dan tidak begitu menghiraukan mode busana yang sedang menjadi trandy, sebab yang terpenting adalah bagaimana berbusana yang sesuai dengan norma-norma agama, dan menjauhi yang keluar dari norma agama tersebut. Pemahaman dan pola berbusana semacam ini sangat sesuai dengan etika Islam. Mahasiswi yang bergabung dengan HMI, IMM dan PMII yang memahami pola busana dengan lebih longgar, mereka ekspresikan dengan pilihan pola busana yang tidak terlalu longgar, namun dapat menurut aurat. Pilihan mereka terhadap pola busana seperti yang mereka kenakan juga didasari oleh pemahaman keagamaan yang moderat, sebab di dalam berbusana, di samping harus memperhatikan norma-norma agama, juga perlu memperhatikan mode busana yang sedang menjadi trand agar tidak ketinggalan zaman. Artinya, bagaimana bisa tampil trandy tetapi juga religius. Dengan prinsip dapat menutup aurat dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh, dan tidak transparan, maka pamaham keagamaan dan pola berbusana mahasiswi yang tergabung dengan HMI, IMM dan PMII juga tidak keluar dari etika Islam. Sedangkan mahasiswi yang memahami bahwa busana mahasiswi seharusnya yang mengikuti mode dan trandy, mereka ekspresikan dengan lebih memilih pola berbusana yang ketat/transparan, sebab bagi mereka tampil trendy dan 129 mengikuti mode-lah yang diutamakan. Maka yang nampak adalah pola berbusana yang ketat, memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh, transparan dan menor. Pemahaman dan pola berbusana dengan mengesampingkan apakah itu larangan atau dibolehkan oleh agama, apakah sebagai tuntutan etika Islam atau tidak, didasari oleh pemahaman keagamaan yang liberal, dan ini sangat bertentangan dengan etika Islam. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman keagamaan dan pola berbusana mahasiswi IAIN Walisongo yang mereka ekspresikan dengan model busana yang dikenakan adalah; pertama, faktor organisasi yang mereka ikuti, di antaranya yang melarang memakai busana ketat dan transparan, atau sebaliknya tidak ada larangan. Kedua, faktor pemahaman keagamaan, seperti pemahaman mahasiswi KAMMI yang sangat ketat, pamahaman mahasiswi yang bergabung dengan HMI, IMM dan PMII yang relatif lebih longgar, dan pemahaman mahasiswi yang bergabung dengan UKM Music, Teater dan Mawapala yang kurang memperhatikan busana yang ditekankan oleh etika Islam. Ketiga, faktor penampakkan identitas yang bisa dilihat dengan model tampilan mahasiswi yang bergabung dengan KAMMI dengan busana longgar sebagai cermin dari pribadi yang berbudi pekerti luhur, shalihah, ataupun mahasiswi yang mengenakan busana ketat yang mengesankan sebagai mahasiswi yang dapat tampil trendy dan gaul. Keempat, faktor kebiasaan, misalnya karena terbiasa memakai busana longgar, tidak terlalu longgar, ataupun memakai busana ketat, ditambah karena patron cliant dari senior-seniornya, ataupun 130 teman satu kost. Kelima, faktor tidak adanya sangsi pelanggaran busana oleh pihak IAIN, sehingga mahasiswi kurang memperhatikan etika berbusana yang dikehendaki oleh IAIN. B. Saran-saran Berdasarkan penelitian penulis terhadap Etika Berbusana Mahasiwi IAIN Walisongo Semarang, disarankan kepada: 1. Mahasiswi yang memahami dan memilih pola berbusana tertentu, seharusnya tidak sebatas penampakan identitas, akan tetapi benar-benar sebagai salah satu penjaga kehormatan mahasiswi perguruan tinggai dengan label Islam dengan memperhatikan etika dan estetika. Dengan demikian akan mengesankan pribadi mahasiswi yang mandiri, cerdas, religius, tetapi tetap trendy, tidak hanya mengitu mode saja yang ingin tampil trendy. 2. Pihak IAIN sudah saatnya melakukan perbaikan-perbaikan aturan etika berbusana mahasiswa yang diikuti pelaksanaan dan pemeberian sanksi pelanggaran berbusana, sehingga IAIN benar-benar bisa mencitrakan etika Islam, di samping melakukan himbauan-himbauan moral oleh seluruh sivitas akademika IAIN. 3. Pihak-pihak yang intens dengan pendidikan Islam, hendaknya memperhatikan banyak aspek sebagai garapan pendidikan Islam termasuk dalam etika berbusana, sehingga akan mengesankan bahwa pendidikan 131 Islam benar-benar mencitrakan anak didiknya sebagai pribadi yang luhur dan beretika. C. Kata Penutup Alhamdulillah, berkat petunjuk dan pertolongan Allah S.W.T. penulisan tesis ini dapat selesai walaupun banyak menemui berbagai kesulitan. Karena tesis ini masih cukup sederhana dan jauh dari sempurna, maka dengan rendah hati penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan tesis ini. Akhirnya hanya kepada Allah penulis memohon rahmat dan hidayah-Nya, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. 132 DAFTAR PUSTAKA Abdullah, M. Amin, Filsafat Etika Islam; Antara Al-Syathibî dan Kant, Bandung: Mizan, 2002. Abdullah, Shodiq, “Corak Pemikiran Keagamaan Mahasiwa IAIN Walisongo Semarang” dalam Jurnal Penelitian Walisongo, Volume XI, Nomor 2 Nopember, 2003. Affandi, Lisyani, Tata Busana 3, Bandung: Ganeka Exact, 1996. Al-Albani, Nashiruddin, Jlbab al-Mar’ah al-Muslimah fi al-Kitâb wa al-Sunnah, Yordania: Al-Maktabah al-Islamiyah, 1413 H. Al-Alusi, Mahmud, Ruh al-Ma’ani, Jilid XXII, Cairo: al-Muniriyyah, 1985. Al-Baqi, Ibrahim ibn Umar, Nazhm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar, Jilid V, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1995. Al-Barazi, Muhammad Fuad, Hijab al-Mar’ah al-Muslimah, Jilid II, Riyadh: Adhwa al-Salaf, 1999. Al-Bukhâri, Muhammad bin Ismail, Shahîh Bukhâri, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th. Al-Ghazâlî, Abû Hamid, al-Munqidh min al-Dhalal, Istambul: Hakikat Kitabevi, 1984. , Khulûq al-Muslim, Cairo: Dâr al-Kutub al-Hadîtsash, 1974. Ali, Fachry, “Kontiuitas dan Pencerahan: Catatan Sejarah Sosial Budaya Alumi IAIN” dalam Komaruddin Hidayat dan Hendro Prasetyo (ed.), Problem dan Prospek IAIN, Antologi Pendidikan Tinggi Islam, Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam-Dirjen Bimbaga Islam DRPAG RI, 2000. Ali, Mukti, Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini, Jakarta: Rajawali Press, 1988. Al-Isfahani, al-Raghib, Mu’jam al-Mufradat Alfadz al-Qur’ân, disunting oleh Nadim Mars’ashli, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th. Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, Fiqh Wanita,Bandung: Gema Insani Press, 2002. 133 Al-Jaziri, Abd al-Rahman, al-Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah, Beirut: Dâr alFikr, t.th. Al-Kurdi, Ahmad al-Hajji, Hukum-hukum Wanita dalam Fiqh Islam, Surabaya: Dimas, t.th. Al-Maududi, Abû A’la, al-Hijab, Beirut: Dâr al-Firk, t.th. Amin, Qasim, Tahrir al-Mar’ah, Mesir: Percetakan Muhammad Zakiy al-Din, 1347 H. Al-Sa’dawi, Nawal, dan Hibah Ra’uf Izzat dalam al-Mar’ah, Wa al-Din wa alAkhlak, Mesir: Dâr al-Fikr al-Mu’ashir, 2000. Al-Turmudzî, Sunan al-Turmudzî, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th. Al-Zuhaily, Wahbah, Ushûl al-Fiqh al-Islami, Jilid I, Beirut: Dâr al-Fikr, 1986. Amin, Ahmad, Al-AKhlak, terj. Farid Ma’ruf, “Etika”, Bandung: Bulan Bintang, 1975. Amin, M. Darori, “Norma-norma Etika Islam”, dalam Jurnal Teologia, Volume 12, Nomor 3, Oktober 2001. Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 1997. Arkoun, Mohammad, al-Islam al-Akhlaq wa al-Siyasah, Beirut: Markaz al-Inma’ al-Qaumi, 1990. , Tarikhiyyah al-Fikr al-Arabi al-Islami, Beirut: Markaz al-Inma’ alQaumi, 1990. Arman, Sri Rahayu, “Jilbab; Antara Kesucian dan Resistensi”, dalam Http://www.Islamlib.com. Arwi, Abdullah, al-‘Arab wa al-Fikr al-Tarikhi, Beirut: Markaz Tsaqafi al-Arabi, 1973. Assyaukanie, Luthfi, Tipologi dan Wacana Pemikiran Arab Kontemporer, dalam http://www.Islamlibral.com. Asyur, Muhammad, Maqashid al-Syri’ah al-Islamiyah, Kairo: Dâr al-Katib, 1967. Blackburn, Somon, Being Good; Pengantar Etika Praktis, terj. Hari Kusharyono, Yogyakarta: Jendela, 2004. Crapps, Robert W., (Ed.), An Introduction to Psycology of Religion, terj. Agus M. Hardjana “ Perkembangan Kepribadian dan Keagamaan, Yogyakarta: Kanisius, 1994. 134 Dawud, Abû, Sunan Abû Dawud, Beirut: Dâr al-Ihya al-Sunnah al-Nabawiyah, t.th. Dhavamony, Phenomenology of Religion, terj. Sudiarja, dkk., Yogyakarta: Kanisius, 1995. Djamhari, Agama dalam Perspektif Sosiologis, Bandung: Alfabeta, 1993. El-Gundi, Fadwa, Veil: Modesty, Privacy dan Resistance, terj. Mujiburohman “Jilbab: Antara Kesalehan, Kesopanan dan Penawanan”, Jakarta: Serambi, 2003. Fakhri, Majid, Ethical Theories in Islam, terj. Zakiyuddin Baidhawi “Etika dalam Islam”, Jakarta: Pustak Pelajar, 1996. Hajaj, Muslim ibn, Shahîh Muslim, Beirut: Dâr al-Ilm, t.th. Hamersma, Harry, Tokoh-tokoh Filsafat Barat Modern, Jakarta: Gramedia, 1986. Hanafi, Hasan, al-Turâs wa al-Tajdid Mauqifuna min al-Turâs al-Qadim, Beirut: Al-Mu’assasah al-Jami’ah li al-Dirasat wa al-Nasyr wa al-Tauzi, 1992. Herfanda, Ahmadun Yosi, “Membongkar Ruang Sempit Sastra Religius” dalam Http://www.republika.co.id. Hidayat, Komaruddin, dan Hendro Presetyo, Problem dan Prospek IAIN, Antologi Pendidikan Tinggi Islam, Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam-Dirjen Bimbaga Islam DRPAG RI, 2000. Ilyas, Yunayar, Kuliah Akhlak, Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPII), 2004. Izutzu, Toshihiko, Ethico-Religious Concepts in the Qur’an, terj. Agus Fahri Husein “ Konsep Etika Religius dalam al-Qur’ân, Yogyakarta: Tiara Wacana, 3003. Jabali, Fuad, dan Jamhari, IAIN dan Pembaruan Islam di Indonesia, Jakarta: Logos, 2002. Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: Gramedia, 1983. Lari, Sayid Mujtaba Musawi, Ethics and Spiritual Growth, terj. M. Hasyim Assagaf ”Etika dan Pertumbuhan Spiritual”, Jakarta: Lentera Basritama, 2001. Majah, Ibn, Sunan Ibn Majah, Beirut: Dâr al-Firk, t.th. 135 Mandhur, Ibn, Lisan al-Arab, Mesir: Dâr al-Ma’arif, t.th. Mernisi, Fatima, Pemberontakan Wanita, terj. Yogyakarta: LKiS, 1996. Muhadjir, Noeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989. Muleong, Lexy J., Metodelogi Penelitian kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995. Munawir, Ahmad Warson, Kamus al-Munawir Arab-Indonesia, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir Krapyak, 1984. Musa, Muhammad Yusuf, Filsafat al-Akhlak fi al-Islam, Cairo: Maktabah alKhanji, 1963 Musahadi, dkk., IAIN Walisongo; Mengeja Tradisi Merajut Masa Depan, Semarang: Puslit IAIN Walisongo Bekerja Sama dengan CV. Putakindo Pratama, 2003. Poespoprodjo, W., Filsafat Moral; Kesusilaan dalam Teori dan Praktek, Bandung: Pustaka Grafika, 1999. Salam, Burhanuddin, Etika Individual; Pola Dasar Filsafat Moral, Jakarta: Rineka Cipta, 2000. Shahrur, Muhammad, Metodologi Fiqh Islam Kontemporer, terj. Yogyakarta: Elsaq, 2004. Shihab, M. Quraish, Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2004. , Wawasan al-Qur’ân, Bandung: Mizan, 1998. Shubhi, Ahmad Mahmud, Al-Falsafah al-Akhlaqiyyah fi al-Fikr al-Islami; al‘Aqliyyun wa al-Dzauqiyyun aw al-Nadzar wa al-Amal, Beirut: Dâr alNahdhah al-Arabiyah, 1992. Suhartono, Suparlan, Dasar-dasar Filsafat, Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2004. Suryabrata, Sumadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983. Suseno, Frans Magnis, Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral, Yogyakarta: Kanisius, 1987. 136 Syalabi, Ra’uf, Syeikh al-Islam Abdul Halim Mahmud, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1982. Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur’ân, al-Qur’ân dan Terjemahnya, Madinah: Mujamma’ al-Malik Fahd li Thiba’at Mushaf al-Syarif, 1418 H. Tim Penyusun Kamus Dekdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jaakarta: Balai Pustaka, 1990. Titus, Harold H., dkk., Persoalan-persoalan Filsafat, Jakarta: Bulan Bintang, 1984. Willy, Markus, dkk., Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Indonesia, IndonesiaInggris, Surabaya: Arloka, 1997. Wirawan, Sarlito, Kajian Islam tentang Berbagai Masalah Kontemporer, Jakarta: Lembaga Penelitian IAIN Syarif Hidayatullah 1988. Yalchan, Miqdad, al-Ittijah al-Akhlaqi fi al-Islam, Cairo: Maktabah al-Khanji, 1973. 137 ANGKET PENELITIAN Petunjuk Pengisian 1. Pilihlah jawaban sesuai pemahaman Saudara 2. Semua jawaban tidak ada yang salah 3. Penelitian ini untuk kepentingan akademik Identitas Responden Nama Tempat & Tgl. Lahir Fakultas Angkatan Organisasi Kemahasiswaan : : : : : ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... (Misalnya PMII, HMI, KAMMI, IMM, atau organisasi intra, tulis salah satu saja) PERTANYAAN-PERTANYAAN Pemahaman tentang Busana 1. Apa yang Anda pahami tentang busana muslimah? a. Harus menutup seluruh aurat kecuali muka dan telapak tangan b. Harus yang longgar dan tidak boleh sampai menampakkan lekuk-lekuk tubuh atau ketat c. Boleh ketat yang penting menutup aurat d. Bebas sesukanya yang penting mengikuti mode (trend) atau asal kelihatan gaul 2. Apa yang Anda pahami tentang memakai jilbab? a. Wajib menurut agama b. Sunnah menurut agama c. Identitas muslimah d. Etika muslimah dalam berbusana 3. Menurut Anda apabila seorang muslimah tidak memakai jilbab, apakah termasuk tidak beretika? a. Beretika b. Tidak beretika c. Biasa-biasa saja Implikasi dari Pemahaman tentang Busana 1. Apakah Anda memakai busana sesuai yang Anda pahamai? a. Memakai b. Tidak memakai c. Kadang-kadang memakai 138 2. Apakah Anda memakai jilbab? a. Memakai b. Tidak memakai c. Kadang-kadang memakai 3. Bagaimana perasaan Anda jika di luar jam kuliah, misalnya jalan-jalan tidak memakai jilbab? a. Merasa tidak percaya diri b. Merasa tidak beretika c. Tidak tahu, karena selalu memakai jilbab walaupun di luar kuliah kecuali di rumah (kost) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pola Berbusana Mahasiswi IAIN 1. Apa yang mempengaruhi Anda memakai busana seperti yang Anda pahami? a. Karena perintah agama untuk menutup aurat b. Karena ikut mode (trend) atau ikut-ikutan c. Karena aturan organisasi yang saya ikuti d. Karena peraturan di IAIN 2. Apa yang mempengaruhi Anda memakai jilbab seperti yang Anda pahami dan Anda pakai (misalnya jilbab yang Anda pakai ukurannya lebar, kecil, atau wajar-wajar saja) a. b. c. d. Karena perintah agama Karena aturan organisasi Karena ikut mode (trend) Karena tidak percaya diri jika tidak memakai seperti yang saya pakai 139