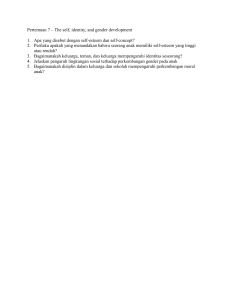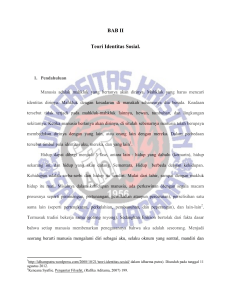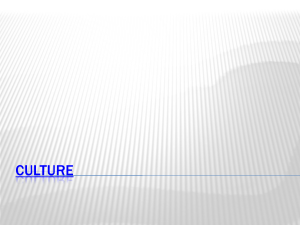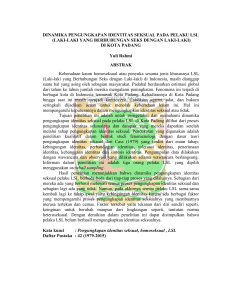“Membali di Lampung” Studi Kasus Identitas Kebalian di Desa
advertisement

BAB II. IDENTITAS dan KEBALIAN Dua tema utama yang akan diuraikan dalam bab ini sebagai sebuah tinjauan literatur adalah diskusi tentang Identitas dan kebalian. Dalam tema identitas akan didiskusikan berbagai pemikiran, konsep atau pun teori tentang Identitas. Pendiskusian identitas dimaksudkan untuk memperkaya pemahaman atas Identitas itu sendiri sebagai sebuah konsep atau teori, khususnya pembentukan atau konstruksi (bangunan) Identitas. Diskusi tentang kebalian akan didiskusikan dengan singkat beberapa literatur yang relevan dengan konteks penelitian – ada banyak literatur tentang Bali, tidak semua penad untuk didiskusikan, dan beberapa di antaranya sudah terintegrasi dalam bab-bab selanjutnya. Tentang Identitas Diskusi ini akan diawali dengan pemikiran Manuell Castells. Acuannya pada karya Castells yang berjudul “The Power of Identity4”. Agar tidak terjadi keserampangan dalam mendiskusikan tentang Identitas, perlu diketahui secara singkat konteks dari karya Castells tersebut. Pertama, “The Power Identity” merupakan volume kedua atau merupakan kelanjutan dari volume pertama. “The Power of Identity” adalah kelanjutan dari “The Rise of Network Society5” (volume pertama). Sebagai sebuah rangkaian (serial) ada keterjalinan antara “The Rise of Network Society” dengan “The Power of Identity”; Kedua, dari kedua volume tersebut dapat diketahui bahwa yang mendasari “The Power Identity” adalah “The Rise of Network Society”. Kemudian, dari kedua volume ini Castells mengakhirinya dengan volume ketiga yang berjudul “End of Millennium”6. Jadi, uraian tentang Identitas dalam karya Castells lebih terampat pada 4 Manuel, Castells. (2002), The Information Age: Economy, Society and Culture, Volume II: The Power of Identity, Oxford: Blackwell. Catatan penulis: terbit pertama kali tahun 1997. 5 Manuel, Castells. (2000), The Information Age: Economy, Society and Culture, Volume I: The Rise of the Network Society, Oxford: Blackwell. Catatan penulis: terbit pertama kali tahun 1996. 6 Manuel, Castells. (2004), The Information Age: Economy, Society and Culture, Volume III: End of Millennium, Oxford: Blackwell. Catatan penulis: terbit pertama kali tahun 1998. 15 volume kedua – dan sebenarnya Castells tidak secara total fokus kepada identitas di volume kedua karena identitas hanya menjadi salah satu bagian dari Trilogi Castells dalam “The Information Age” (terutama di trilogi yang kedua, itu pun hanya di bagian awal dari keseluruhan “The Power of Identity”). Mengapa? Karena yang menjadi perhatian utama Castells dalam tema besar trilogi “The Information Age” adalah terfokus dengan restrukturisasi masyarakat kapitalis (capitalist civilization), dengan globalisasi dan perubahan organisatoris di dalamnya, sejak tahun 1960-an, yang didukung oleh pembangunan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, hancurnya komunisme Sovyet, dan klaim representatif bahwa masyarakat kapitalis yang sudah terrestrukturasi tersebut sebagai sebuah alternatif bagi masyarakat (sipil) modern (modern civilization)7. Konteks besar dalam penguraian Castells, terutama tentang Identitas (dalam The Power of Identity), adalah masyarakat jaringan (network societies) dalam sebuah era informasi (the information age) – sebuah era atau masa di mana revolusi teknologi tidak hanya melahirkan sebuah masyarakat jaringan8, tapi juga menyebabkan berbagai macam perubahan dalam bidang teknologi informasi, ekonomi, politik, kemasyarakatan (hubungan sosial), dan kebudayaan. Seperti yang dikemukakan Castells (2000) mengatakan bahwa: “Our societies are increasingly structured around a bipolar opposition between the Net and the self9”, dan Castells (2002) bahwa: “Our world, and our lives, are being shaped by the conflicting trends of globalization and identity10”. Tanpa 7 Lihat: McGuigan, Jim. (2006), Modernity and Postmodern Culture, New York: Open University Press. Hlm. 115-136 dalam bab: “The Information Age”. 8 Jaringan atau “The Net” yang dimaksudkan oleh Castells (2000) tidak hanya secara khusus ditempatkan pada Internet, tapi juga, tercakup model jaringan (network) masyarakat dan kebudayaan secara umum, di mana menransformasikan realitas kelembagaan dan kondisi (riil) sehari-hari masyarakat di dunia. 9 Castells (2000), op.cit. hlm.3. Terjemahan dari kalimat ini mengutip Putranto (2004, hlm.86): “Masyarakat kita semakin terstruktur seputar oposisi dwi-kutub, yaitu kutub Jaringan dan kutub diri”. 10 Castells (2002), op.cit. hlm.1. Terjemahan mengutip Putranto (2004, loc.cit): “Dunia dan hidup kita sedang dibentuk oleh tren-tren yang saling bergesekan, yaitu globalisasi dan identitas.” 16 mengetahui konteksnya – bisa saja – pemahaman identitas atas pemikiran Castells bisa keluar dari batasan-batasan atau pengkondisian identitas yang dimaksudkan oleh Castells. Jika konteksnya berada pada sebuah masyarakat jaringan, maka – tanpa perlu dijelaskan – bahwa masyarakat yang dimaksudkan lebih tertuju pada masyarakat yang modern. Modern dalam arti, singkatnya, sudah akrab dengan teknologi informasi – khususnya internet – yang memintal masyarakat dalam sebuah masyarakat jaringan. Karenanya, menjadi tidak tepat jika konteks identitas dalam masyarakat jaringan digunakan dalam sebuah masyarakat yang belum mendapatkan atau mampu memanfaatkan teknologi informasi. Apa yang sebenarnya menjadi pokok-pokok untuk diskusi tentang Identitas berdasarkan karya Castells, The Power of Identity? Dalam subbab “The Construction of Identity” di bab pertama “The Power of Identity”, Castells mengemukakan bahwa identitas merupakan sumber makna (pemaknaan) dan pengalaman orang. Proses pengkonstruksian makna tersebut didasarkan atas sebuah atribut kultural, atau terkait dengan seperangkat atribut kultural, di mana diprioritaskan di atas sumber-sumber pemaknaan yang lain. Ini yang menyebabkan identitas bersifat majemuk / jamak (plurality of identities), karena identitas sebagai sumber pemaknaan dan pengalaman, serta atribut kultural diperuntukkan bagi seorang individu, atau sebuah kumpulan aktor (collective actor). Akibatnya, kejamakan identitas menjadi sumber tekanan dan kontrakdiksi baik dalam self-representation maupun social action. Ini yang menyebabkan mengapa identitas harus dibangun, seperti yang umum disebutkan para sosiolog, sebagai peran, dan seperangkat peran (roles, and role-sets). Meskipun demikian, Castells berpendapat bahwa identitas lebih dominan sebagai sumber pemaknaan daripada peran. Identitas dikonstruksikan oleh aktor melalui sebuah proses yang disebut individuisasi (individuation), terkait dengan identitas sebagai sumber makna bagi aktor itu sendiri. Atau, dalam pandangan Giddens (1991) 11 identitas sebagai sebuah proyek. Dengan kata lain, aktor atau agen tersebut tidak bisa dilepaskan dari 11 Giddens, Anthony. (1991), Modernity and Self-Identity, Cambridge: Polity Press. 17 struktur yang ada – yang diperkuat dengan pernyataan Connolly (2000)12 terkait masyarakat jaringan dan struktur bahwa kehidupan politik identitas dalam masyarakat modern tidak dapat lepas dari struktur politik global. Lebih lanjut, Castells berpendapat bahwa identitas yang (dapat dikatakan) berasal dari institusi-institusi dominan dapat menjadi identitas ketika dan jika ada proses internalisasi oleh aktor sosial, dan mengkonstruksikan makna yang ada melalui proses internalisasi. Dalam bukunya The Power of Identity – terkait dengan pumpunan Castells pada masyarakat jaringan – Castells dengan tegas memfokuskan kajian tentang identitas dalam konteks masyarakat jaringan pada identitas kolektif (collective identities). Hal ini dikarenakan bahwa di dalam masyarakat jaringan pemaknaan individu melewati ruang dan waktu – terpintal dalam sebuah jaringan. Tanpa mengabaikan fakta bahwa identitas kolektif tersebut – seperti dalam masyarakat jaringan – merupakan pintalan dari identitas individu. Dengan kata lain, dilihat dari bentuknya, identitas dapat dipilah menjadi identitas individu dan identitas kolektif. Castells sependapat, berdasarkan fakta dan dalam perspektif sosiologi, bahwa semua identitas adalah terkontrusksi (dikonstruksikan, dibentuk). Bahan-bahan atau material pengkonstruksian tersebut adalah berasal dari sejarah, letak geografis, biologi, institusiinstitusi produktif dan reproduktif, collective memory dan fantasi personal, serta dari kekuasaan aparatur-aparatur dan syariah keagamaan (kitab). Terakhir, Castells merumuskan bangunan identitas berdasarkan bentuk dan asal usulnya menjadi tiga, yaitu: (1) Legitimizing identity, atau identitas yang sahih, seperti otoritas (authority) dan dominasi; (2) Resistance identity, atau identitas perlawanan, sebagai bentuk perlawanan atas dominasi, contohnya adalah politik identitas; (3) Project Identity, atau identitas proyek, seperti feminisme – ketika aktor-aktor sosial dengan sumber daya kulturalnya membangun sebuah identitas baru untuk mendapatkan kembali posisinya di masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, pokok-pokok tentang Identitas dari pemikiran Castells, di antaranya adalah: (1) identitas sebagai sumber makna dan pengalaman; (2) atribut kultural sebagai basis konstruksi 12 Connolly, William E. (2000), “Identity and Difference in Global Politics”, dalam Nash, Kate. (Ed.), Readings in Contemporary Political Sociology, Oxford: Blackwell. Hlm.346. 18 makna; (3) identitas bersifat jamak; (4) seperangkat peran; (5) proses individuisasi; (6) internalisasi; (7) bentuk identitas: individu dan kolektif; (8) material konstruksi identitas; (9) bentuk dan asal usul identitas. Identitas menjadi sangat kompleks dalam proses pembentukan atau pengkonstruksiannya, dalam kasus Castells terpumpun pada masyarakat jaringan. Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa masyarakat jaringan dapat dikatakan sebagai masyarakat modern yang telah memasuki era informasi – yang juga telah mengalami dan menikmati secara langsung revolusi teknologi. Tentu, apa yang diuraikan oleh Castells ini cukup kompleks dan mumpuni untuk konteksnya, dan ini bukan sebuah asas semesta atas diskusi tentang Identitas. Dengan kata lain, pemikiran Castells cukup penad untuk dijadikan rambu dalam sebuah kerangka pemikiran teoritis tentang Identitas. Karena tema identitas menjadi tema yang menarik perhatian banyak pemikir (akademisi), akan menjadi sempit jika tidak menyertakan pemikir lainnya dalam diskusi tentang Identitas ini –bagaimana pun setiap pemikir memiliki perbedaan perspektif tentang Identitas. Karya berikutnya yang akan dikaji adalah karya sosiolog strukturalis bernama Peter J. Burke yang ditulis bersama istrinya, Jan E. Stets berjudulkan “Identity Theory”13. Agar tidak terpesona dengan grand title buku tersebut, terlebih dahulu diuraikan sekilas konteks atau latar belakang buku tersebut. Buku ini – Identity Theory – (tampaknya) dapat dikatakan seperti buku teks tentang teori identitas. Metode penelitian yang dikembangkan untuk buku ini adalah kuantitatif dengan survey ke banyak responden. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sangat terukur untuk membuktikan hipotesa-hipotesa yang diajukan oleh kedua penulis ini tentang Identitas. Respondennya jelas adalah masyarakat Barat. Displin ilmu yang digunakan untuk Identity Theory ini adalah sosiologi, sesuai dengan latar belakang keilmuan kedua penulis, terutama Burke. Letak perbedaan antara karya Burke dan Stets dengan Castells sebenarnya terletak pada fokus kajiannya. Jika Castells merampatkan kajiannya pada identitas kolektif, maka Burke dan Stets merampatkannya 13 Burke, Peter. and Stets, Jan E. (2009), Identity Theory, New York: Oxford University Press. 19 pada identitas personal. Alasan yang dikemukakan oleh Burke dan Stets sangat jelas, bahwa esensi atau dasar dari identitas terletak pada identitas personal – sebuah kenyataan yang diakui oleh Castells, tetapi Castells memiliki fokus di identitas kolektif karena konteks yang dipilih adalah masyarakat jaringan. Basis teori yang digunakan oleh Burke dan Stets untuk membangun Identity Theory adalah interaksionisme simbolik (symbolic interactionism), agen dan struktur sosial sebagai penyangganya – terkait bahwa pemfokusannya pada level personal (identitas individu) tidak bisa dilepaskan dari peran agen (aktor) dan struktur yang mendominasi si individu. Melalui interaksionisme simbolik, Burke dan Stets dalam menyentuh kedalaman Identitas yang berasal dari individu, yaitu dengan menggunakan instrumen utama the self, language, sign, and symbols, dan interaction yang menjadi fondasi interaksionisme simbolik. Kemudian, oleh Burke dan Stets interaksionisme simbolik ini ditopang dengan teori control system, namun basis utamanya tetap interaksionisme simbolik. Terkait dengan agen atau aktor – yang menjadi fokus kajian – Burke dan Stets berpendapat bahwa perbedaan antara person dan agent pusat teori identitas, di mana dalam teori identitas, sebuah identitas adalah seorang agen, dan setiap orang memiliki banyak identitas (lebih dari satu identitas)14. Ini yang mempertegas keduanya untuk tetap kukuh pada perspektif interaksi simbolik struktural untuk membidani dan mengkonstruksikan teori identitas, dan berpandangan bahwa sebuah identitas juga merupakan sebuah kontruksi teoritis15. Perbedaan yang mencolok antara Castells dengan Burke dan Stets adalah pada basis identitasnya. Castells lebih menyeluruh dalam menyusun dan menguraikan basis identitas. Burke dan Stets membasiskan identitas pada peran (role), grup / kelompok (group), dan perorangan / individu (person). Meskipun terlihat sangat sempit dan kaku, namun basis identitas yang digunakan Burke dan Stets tidak dapat dilepaskan dari fondasi teori yang digunakannya, serta metode kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan validitas data untuk teori identitasnya. Dengan kata lain, dalam teori identitasnya, Burke dan Stets menjadikan identitas itu benar14 15 Burke dan Stets (2009), op.cit., hlm. 8. Burke dan Stets (2009), op.cit., hlm. 8-9. 20 benar terstruktur dengan rapi terhadap identitas individu melalui interasi simbolik struktural-nya, dan dengannya teori identitas dikontruksikan. Keunggulan dari pendekatan yang digunakan oleh Burke dan Stets adalah pada ketegasan dan kejelasan tentang Identitas yang dikontruksikan melalui pendekatan interasionisme simbolik-nya. Sasarannya tepat untuk membidik identitas itu sendiri yang berhulu pada individu. Ini yang menyebabkan pengkontruksian teori identitas yang dilakukan keduanya menjadi tegas dan jelas. Tepat digunakan sebagai buku teks, tetapi dengan catatan, bahwa teori ini dibangun pada satu perspektif dan satu konteks yang sangat terbatas pada masyarakat modern yang – menurut mereka – sudah secara rapi terstruktural. Studi Burke dan Stets tampaknya terlalu kaku. Keduanya sangat mengacu pada structural simbolic interaction sebagai dasar atau akar dalam membangun kerangka teori Identitas dengan metode penelitian yang sangat terukur (kuantitaf- survey dengan fokus objek personal). Ulasan yang lebih menyeluruh sebenarnya dilakukan oleh James E. Cote dan Charles G. Levine tentang Identity Formation, Agency, dan Culture16. Letak perbedaannya terletak pada aspek culture – tanpa dipungkiri bahwa Cote dan Levine pun tetap menggunakan teori struktur sosial, agensi, simbolic interaction dalam bukunya dengan berakarkan psikoanalisa sebagai pioner teori identitas (seperti yang dikembangkan Erikson17 berangkat dari fondasi self yang dibangun oleh Freud), kemudian dikembangkan melalui sebuah sintesis psikologi sosial. Hal ini dapat dilihat dari kerangka kerjanya dalam memahami identity formation, Agency, dan Culture yang didasarkan pada hubungan yang saling mempengaruhi antara social structure, interaction, dan personality, yang di dalam hubungan tersebut terdapat socialization dan social control, dan, internalization (ego synthesis abilities)18. Sebaliknya, hubungan antara personality, interaction, dan social structure, yang di dalamnya terdapat 16 Cote, James E. & Levine, Charles G. (2002), Identity Formation, Agency, and Culture: A Social Psychological Synthesis, London: Lawrence Erlbaum Associates. 17 Karya terkenal Erikson yang banyak dirujuk untuk studi identitas adalah: Erikson, Erik H. (1963), Childhood and Society, New York: W.W. Norton & Co. 18 Cote, James E. & Levine, Charles G. (2002). Op.cit., hlm. 6-9. 21 presentation of self (ego executive abilities) dan social construction of reality (objectivation)19. Hubungan saling mempengaruhi dua arah ini yang menyebabkan adanya subjektivitas yang bermuara pada objektivitas, dan terus berulang. Fokus Cote dan Levine sebenarnya sama dengan Burke dan Stets, yaitu identitas personal – dapat dilihat pada penggunaan interaksi simbolik yang membentuk (memformasikan) identitas oleh agen yang terstruktur. Baik karya Burke dan Stets maupun Cote dan Levine, keduanya bisa dipadukan sebagai buku teks tentang Identitas, namun dalam posisi kajian yang merampat pada identitas personal sebagai identitas secara keseluruhan. Meskipun demikian, kedua karya ini terkait dengan identitas personal (individu) sebagai cara melihat identitas secara keseluruhan. Ulasan dalam kedua karya tersebut masih belum menyentuh kedalaman tentang Identitas itu sendiri. Cara lain melihat Identitas lebih mendalam adalah dengan perspektif psikologi / psikoanalisa (sosial), yaitu melalui sebuah cerita atau narasi, seperti yang dikembangkan oleh McAdams, dkk. (2006)20. Dengan kata lain, mereka ingin melihat identitas dari kedalamannya sendiri, “self”, yang dapat disampaikan melalui sebuah cerita atau narasi diri. Melalui sebuah cerita seseorang bisa menarasikan dirinya (self), atau, mengidentifikasikan dirinya seperti apa. Dengan kata lain, mengkonstruksikan identitas dirinya (identitas personal) melalui sebuah cerita. Karenanya, aspek psikologi (khususnya psikoanalisa yang dikembangkan oleh Freud dan Erikson) menjadi sangat penting. Fokusnya sama-sama personal, baik Burke & Stets, Cote & Levine maupun McAdams, dkk. Hanya saja, peran struktur sosial yang sebenarnya sedikit banyak memiliki dominasi atas individu dalam mengidentifikasikan dirinya (identitasnya) menjadi terabaikan. Kedalaman atas identitas personal itu dapat tercapai dengan sebuah narasi melalui pisau psikologi (dan, atau psikoanalisa). Bagi Chris Barker, keempat karya ini (dari 19 Cote, James E. & Levine, Charles G. (2002). Loc.cit. McAdams, Dan P., Josselson, Ruthellen., dan Lieblich, Amia. (Ed.). (2006), Identity and Story: Creating Self in Narrative, Washington, D.C.: American Psychological Association. 20 22 masyarakat jaringan sampai narasi), dijadikan sebagai sebuah kerangka pikir tentang Identitas dalam kajian studi kebudayaan21. Karya lain yang menarik untuk didiskusikan adalah karya Richard Jenkins yang berjudul “Social Identity”22. Bila dibandingkan dengan karyakarya pemikir sebelumnya yang telah diulas di atas, karya Jenkins tentang Social Identity atau “Identitas Sosial” adalah karya yang ambigu. Ada sebuah kesalahan yang dinilai cukup fatal, dan ini diakui oleh Jenkins disertai alasannya, bahwa Jenkins sebenarnya tidak membahas tentang “Identitas Sosial”, ia lebih terfokus membahas tentang identitas itu sendiri atau “identifikasi”. Kata “Sosial” yang diletakkan pada “Identitas” sebagai sebuah judul besar buku “Identitas Sosial” atau “Social Identity”, sebenarnya lebih disebabkan (faktor utama) oleh: pertimbangan pemasaran – agar buku ini memiliki nilai jual dan laku di pasaran. Jadi, Jenkins sebenarnya tidak membahas tentang “Identitas Sosial”, tetapi “Identitas” atau “identifikasi”. Tentu, ini akan menjadi masalah jika karya Jenkins ini digunakan oleh pembacanya sebagai acuan atau kerangka teoritis untuk membahas “Identitas Sosial”, padahal, Jenkins sendiri dengan tegas mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak membahas “Identitas Sosial”, melainkan Identitas atau identifikasi, dan kata “Sosial” yang dimasukkan dalam judul besar buku digunakan sebagai pertimbangan marketing (pemasaran) agar karyanya laku di pasaran – mulai dari edisi pertama sampai edisi ketiga . Seperti yang diutarakan oleh Jenkins dalam edisi ketiga “Social Identity”-nya: “Which brings us back to social identity. While this third edition retains the book‟s original title – marketing considerations carry some weight, after all – I prefer, wherever possible, simply to talk about „identity‟ or „identification‟.” 23 21 Lihat: Barker, Chris. (2009), Cultural Studies: Teori dan Praktek (terj.), Yogyakarta: Kreasi Wacana. 22 Jenkins, Richard. (2008), Social Identity: Third Edition, London & New York: Routledge-Taylor&Francis Group. 23 Jenkins, Richard. (2008), op.cit., hlm.17. 23 Argumen yang dikemukakan oleh Jenkins mengapa sebenarnya ia berbicara tentang “identitas” atau “identifikasi”, bukan Identitas Sosial, adalah, pertama, (menurut Jenkins jika argumennya benar) semua identitas manusia, dilihat dari definisinya, merupakan identitas sosial (social identity); kedua, bahwa untuk membangun secara analitik antara “sosial” dan “kultural” merancukan realitas manusia yang sesungguhnya 24. Lalu, definisi apa yang dimaksukan oleh Jenkins yang mendasari bahwa semua identitas manusia adalah identitas sosial? Secara sederhana Jenkins mengambil definisi Identitas (“Identity”) dari The Oxford English Dictionary, di mana bahasa Latin yang menjadi akar dari “Identity” adalah “identitas” (sama seperti Bahasa Indonesia: identitas), yang terdiri dari idem, yang berarti “sama” atau “kesamaan” (the same), dan dua makna dasar: (1) the sameness of object, as in A1 is identical to A2 but not to B1; (2) the consitency or continuity over time that is the basis for establishing and grasping the definiteness and distinctiveness of something. Jadi, tema utama yang dibahas oleh Jenkins “tentang Identitas” – yang berasal dari definisi tersebut – adalah “persamaan” dan “perbedaan”. Melalui “persamaan” dan “perbedaan” ini, Jenkins mengkonstruksikan Identitas “Sosial”-nya. Sama seperti penulis-penulis sebelumnya, Jenkins pun tidak dapat lepas dari interaksi simbolik, terutama untuk menggambarkan persamaan dan perbedaan yang melandasi identitas (level individu), dan struktur sosial. 24 Tulisan lengkapnya dalam Jenkins, Richard. (2008), op.cit., hlm.17. adalah: First, if my argument is correct, all human identities are, by definition, social identities. Identifying ourselves, or others, is a matter of meaning, and meaning always involves interaction: agreement and disagreement, convention and innovation, communication and negotiation. To add the „social‟ in this context is somewhat redundant. Second, I have argued elsewhere that to distinguish analytically betweeen the „social‟ and the „cultural‟ misrepresents the observable realities of the human world. Sticking with the plain „identity‟ prevents me from being seen to do so. 24 Selain Jenkins, ada beberapa penulis lain yang mencoba mengkonstruksikan identitas berdasarkan persamaan (yang diartikan oleh mereka sebagai “identitas”) dan perbedaan – identitas itu menjadi ada karena adanya persamaan dan perbedaan. Berbeda dengan Jenkins dan penulis sebelumnya, kerangka pemikiran yang digunakan untuk mengkontruksikan identitas adalah dengan menggunakan logika (the Science of Logic) dan filsafat Hegel (the Philosophy of Mind dan the Philosophy of Right). Bila dibandingkan dengan Jenkins, tentu kajian dari penulis-penulis ini lebih mendasar (dan tentunya lebih berfilosofi). Tulisan-tulisan mereka terampai dalam sebuah buku berjudul: “Identity and Difference: Studies in Hegel’s Logic, Philosophy of Spirit, and Politic” (editor: Philip T. Grier, 2007)25. Apa yang menarik dari bunga rampai tulisan mereka? Pertama, dengan menggunakan logika Hegel (the Science of Logic), para penulis mencoba secara mendasar memahami Identitas (persamaan) dan perbedaan sebagai landasan yang hakiki tentang identitas itu sendiri. Kedua, setelah logika identitas tersebut diketahui, penulis lain mencoba memahami identitas dengan the Philosophy of Mindnya Hegel. Dengan kata lain, melalui Philosophy of Mind-nya Hegel, ingin dilihat persamaan dan perbedaan tersebut dari aspek psikologisnya – terampatkan pada si individu. Kurang lebih sama seperti dilakukan oleh penulis lain yang menggunakan interaksionis simbolik atau pun narasi. Ketiga, beberapa penulis lain menggunakan Dialektika Hegel untuk memahami persamaan dan perbedaan untuk menggambarkan masyarakat (peoples), gender, dan bangsa-bangsa (nations). Keempat, menggunakan the Philosophy of Right untuk memahami identitas lebih ke aspek politiknya (politik identitas). Singkatnya, para penulis ingin mempertegas konsep “perbedaan” untuk mengkonstruksikan identitas dengan menggunakan logika (dan dialektika) dan filsafat Hegel. Baik Jenkins maupun Grier, dkk., keduanya sama-sama membangun kerangka identitas berdasarkan persamaan dan perbedaan yang menjadi esensi atau hakikat identitas itu sendiri sebagai jati diri – dikatakan sebuah identitas atau jati diri jika ia “berbeda” dengan yang lain. Perbedaan yang mendasar dari 25 Grier, Philip T. (Ed.). (2007), Identity and Difference: Studies in Hegel’s Logic, Philosophy of Spirit, and Politics, New York: State University of New York. 25 keduanya terletak pada alat yang digunakan untuk mengontruksikan identitas, Jenkins lebih menggunakan pendekatan sosiologi, sedangkan Grier, dkk., lebih menggunakan pendekatan filsafat Hegel. Menarik juga untuk didiskusikan tentang Identitas dari para postmodernis dengan pemikiran tentang Identitas yang saling mengisi. Madan Sarup (1996)26 melihat identitas dari aspek kesejarahan yang membentuk identitas. Identitas merupakan sesuatu yang bisa diwarisi. Seperti yang dikemukakan oleh Moya (2000) bahwa: “The difficulty, critics of identity point out, is that identities are constituted differently in different historical contexts“27. Tentu, Sarup pun memahami perdebatan yang ada tentang Identitas, yaitu apakah keterbentukannya melalui sebuah interaksi atau konstruksi. Dua model identitas menurut Sarup (1996)28, yaitu: (1) dari sudut pandang tradisional, bahwa keseluruhan dinamika identitas seperti kelas, gender, dan ras beroperasi secara simultan menghasilkan identitas yang utuh, kebersatuan dan tetap; (2) sudut pandang terkini, bahwa identitas difabrikasi, konstruksi, dalam proses, dan karenanya harus dipertimbangkan aspek psikologi dan faktor sosiologi. Dengan kata lain, identitas yang ada sekarang – dimiliki oleh orang – terfragmentasi, penuh dengan kontrakdiksi-kontradiksi dan ambiguitas. Identitas ras, gender, dan diri (the self) sebagai sesuatu yang utuh, kemersatuan dan tetap, didukung oleh pendapat Alcoff (2006) yang berpendapat bahwa identitas seperti ras, gender, dan diri, adalah identitas yang dapat dilihat atau nyata – kesatuan yang nyata (real entity)29. Pandangan ini didasari atas kritik terhadap politik identitas yang kerap dialamatkan sebagai sebuah permasalahan politik, konseling psikologi, atau kekeliruan metafisik – kritik yang disampaikan oleh akademisi postmodern, politik liberal dan kiri, politisi konservatif, dan lain-lain. 26 Sarup, Madan. (1996), Identity, Culture and The Postmodern World, USA: The University of Georgia Press. 27 Moya, Paula M.L. (2000), “Reclaiming Identity”, dalam Moya, Paula M.L. & Hames-Garcia, Michlael R. (Ed.), Reclaming Identity: Realist Theory and the Predicament of Postmodernism, London: University of California Press. 28 Sarup, Madan. (1996), op.cit. hlm. 14. 29 Alcoff, Linda Martin. (2006), Visible Identities: Race, Gender, and the Self, New York: Oxford University Press. 26 Kebernyataan identitas (sering) bermula dari kenyataan bahwa identitas itu sendiri secara tampak mata dapat dilekatkan (dicapkan, diplotkan) atas diri seseorang, menuntunnya tidak hanya menentukan bagaimana seseorang menerima dan menilai liyan, tapi bagaimana seseorang tersebut diterima dan dinilai oleh mereka (liyan). Kembali ke Sarup (1996)30, terkait dengan studi identitas, ia berpendapat bahwa: pertama, studi identitas harus ditempatkan dalam ruang dan waktu tertentu. Identitas tidak ditempatkan abstrak, tapi selalu dalam relasi pada ruang dan waktu yang telah diberikan. Kedua, studi identitas harus didasarkan atas sesuatu yang disebut bukti, dan harus harus berhati-hati atas metode persepsi. Kemudian, untuk memahami identitas, Sarup (1996)31 menggunakan dua pendekatan. Pendekatan yang objektif berasal dari luar “It is”, kedua, berasal dari dalam “I am”. Perspektif pertama, “It is”, melihat individu dari sudut pandang sosial, sedangkan perspektif kedua, “I am”, individu dalam masyarakat. Dengan kata lain, ada proses identifikasi di dalamnya. Pandangan yang tidak kalah kritisnya dari posmodernis “tentang identitas” adalah seperti yang dikemukakan oleh Haraway (1991)32 bahwa semua identitas (adalah) terbelah. Tidak ada identitas (yang) esensial dari kelas, etnisitas, gender atau pun seksualitas: semuanya berpotensi mencair dan bertransformasi ke dalam bentuk-bentuk yang lain. Identitas yang tetap hanya bisa terjadi melalui sistem-sistem yang mendominasi. Lalu, apa yang menjadi pokok “tentang identitas” dari para postmodernis ini? Sepertinya, mereka ingin memahami identitas lebih ke esensi identitas itu sendiri, keluar dari pakem yang selama ini dipakai oleh “modernis”. Atau, dengan kata lain, mereka ingin keluar dari dominasi “strukturalis” yang mencoba “menaifkan” identitas ke dalam satu bentuk atau format yang baku nan terstruktur – yang berakibat pada ke-identitas-an itu sendiri. Penulis terakhir yang menarik untuk disimak gagasannya tentang Identitas adalah Kwame Anthony Appiah (2005) dengan bukunya yang 30 Sarup, Madan. (1996), op.cit. hlm. 15. Sarup, Madan. (1996), op.cit. hlm. 28. 32 Haraway (1991) dalam McGuidan, Jim. (2006), Modernity and Postmodern Culture: 2nd Edition, London: Open University Press. 31 27 berjudul The Ethics of Identity33. Bila dilihat dari isi atau gagasan dalam bukunya, judul buku tersebut lebih tepat diterjemahkan sebagai “NilaiNilai Identitas” daripada “Etika Identitas”. Ini berangkat dari argumen Appiah bahwa di dalam setiap identitas terdapat nilai-nilai, yaitu nilai-nilai yang bersifat etis atau moral yang mempengaruhi individu atau kelompok yang menggunakan identitas tersebut. Pandangan atau argumen Appiah ini berpijak dari sebuah asumsi bahwa konsep religious toleration dan theory of property-nya Locke, serta slogan human equality dan human right merupakan sebuah “tradisi” yang (diasumsikan) hampir dimiliki setiap manusia, Appiah (2005) berpendapat bahwa itu merupakan “tradisi” yang dapat diasumsikan secara etik individualistik – pada akhirnya, segala suatu merupakan masalah moral karena imbasan individu-individu – jadi, jika itu masalah bangsa-bangsa, atau komunitas-komunitas religius, atau pun keluarga-keluarga, menjadi masalah karena mereka menciptakan sebuah perbedaan kepada masyarakat yang membentuknya. Ini yang mendasari Appiah mengapa identitas itu perlu etika. Individualistik yang melekat pada sebuah identitas – identitas personal maupun sosial – pada akhirnya bermuara pada individu sebagai aktor atau agen yang mengusung keindividualistikan tersebut. Kebebasan atau pun hak asasi manusia yang melekat pada identitas sebagai keindividualistisannya bisa menyebabkan masalah moral, tetapi itu bukan berarti tidak ada etika dalam identitas. Tentunya, hal ini tidak dapat dilepaskan dari diri Appiah yang merupakan seorang Afrika (Ghana), yang pernah melihat bagaimana keindividulistisan dari identitas menyebabkan permasalahan moral di sana. Appiah berpendapat bahwa etika itu ada di dalam identitas. Identitas merupakan sumber nilai yang menjadi etiketnya, dan ada kesamaan nilai dalam identitas, tetapi bekerja dalam cara yang berbeda dalam masyarakat berbeda dengan identitas yang berbeda. Bahwa salah satu nilai universal dari identitas adalah solidaritas (sebagai bagian dari rasa kenyamanan, kepuasan, atau motivasi dan pemaknaan untuk melakukan kebaikan internal komunitas identitas tersebut), tapi cara kerjanya berbeda, dicontohkannya pada masyarakat Yahudi. Identitas kepercayaan, seperti 33 Appiah, Kwame Anthony. (2005), The Ethics of Identity, New Jersey: Princenton University Press. 28 Yahudi, menjadikan kesolidaritasan (dan kesolidan) kelompok orang Yahudi – sama seperti identitas kepercayaan masyarakat lainnya yang membentuk kesolidaritasnya sendiri – tetapi itu hanya berlaku pada orang Yahudi, tidak bagi masyarakat lain. Orang Yahudi tentu tidak akan menerima orang non-Yahudi masuk ke dalam komunitasnya. Selain itu, Appiah berpendapat bahwa nilai-nilai tersebut menjadi satu dalam identitas, di mana menjadi bagian dari nilai-nilai seseorang yang memasukkan identitas tersebut sebagai salah satu identitas dirinya – berangkat dari kenyataan bahwa seseorang bisa memiliki lebih dari satu identitas34. Tentu nilai-nilai tersebut tidak dimiliki orang lain yang tidak memiliki identitas tersebut. Jika sebuah identitas dikonstruksikan oleh pihak tertentu (otoritas atau pun sebuah sistem yang mendominasi), bersifat memaksa dan tanpa adanya pertimbangan nilai-nilai atas identitas tersebut, maka permasalahan identitas akan muncul di aras akar rumput. Manifestasinya adalah melalui politik identitas – oleh Castells (2002) disebut sebagai resistance identity (identitas perlawanan) dan project identity (identitas proyek). Sebenarnya ini bukan gagasan abstrak bahwa identitas bisa dikonstruksikan oleh otoritas tertentu secara sewenang-wenang, baik itu akademisi atau pun penguasa, dan akhirnya menimbulkan aksi politik identitas yang tidak toleran sebagai sebuah perlawanan yang mengusung identitas asalnya (melawan identitas yang terkonstruksi). Ini menjadi kritik tajam dari akademisi (ilmuan) sosial yang berhaluan postkolonial maupun orientalis yang sesungguhnya, bahwa ilmuan Barat atau pun non-Barat sebagai sebuah sistem yang mendominasi, dengan power atau legitimasi intelektual dan kekuatannya, berhasil mengkonstruksikan identitas sebuah bangsa atau kelompok masyarakat tertentu yang mereka cap sebagai dunia ketiga atas sebuah identitas yang tunggal dan bersifat absolut – mengabaikan realitas bahwa di dalam identitas tersebut terdapat nilai-nilai, keragaman (bersifat plural), aspek sejarah dan kultural, dan lain-lain. 34 Appiah, Kwame Anthony. (2005), op.cit. hlm. 24. 29 Amartya Sen (2007)35 dengan tegas mengkritik tesis yang disampaikan oleh Samuel Huntington (1996)36 tentang benturan antar peradaban. Dua kritik utama Sen (2007)37 atas teori peradabannya Huntington (1996) – Sen menyebutkan dua kelemahan Teori Peradaban – yaitu: pertama, satu bentuk yang sangat ambisius dari ilusi tentang ketunggalan – menurut Sen ini adalah kelemahan yang mendasar. Kedua, keserampangan karakterisasi yang diberikan pada peradaban-peradaban dunia – karakterisasi yang mengabaikan bahwa manusia memiliki banyak dimensi. Ilusi tentang ketunggalan ditarik dari asumsi bahwa seseorang tidak mungkin dipahami sebagai satu pribadi dengan banyak afiliasi, tidak pula sebagai orang yang menjadi bagian dari berbagai kelompok yang berbeda-beda, melainkan semata sebagai bagian dari satu kolektivitas tertentu yang memberikannya identitas yang unik dan penting38. Kesempitan cara berpikir – ilusi tentang identitas – yang dikritik oleh Sen bagaimana intelektual menunggalkan identitas sebagai “Barat” dan menunggalkan lawan-nya dengan “Timur” – khususnya yang menjadi perhatian Sen adalah menunggalkan peradaban “Islam” sama halnya menunggalkan peradaban India sebagai “Hindu”. Keserampangan karakterisasi peradaban ini dengan angkuhnya menyingkirkan fakta-fakta sejarah dan fakta nyata bahwa setiap peradaban memiliki banyak karakterisasi atau multidimensi. Tidak mungkin bisa dikerangkeng pada satu pengklasifikasian peradaban tertentu. Tesis ini pun, pada akhirnya menyemai pertikaian global antara peradaban Barat versus peradaban Islam, meskipun tesis ini dibuat sebelum terjadinya aksi terorisme 11 September 2001, tetapi dengan adanya peristiwa tersebut sepertinya menjadikan pembenaran tesis atas kategori tunggal atas warga-warga dunia39. Letak “The Power Identity” – dalam kasus ini kekuatan identitas tunggal yang dikonstruksikan oleh Powerism – yang bersifat 35 Sen, Amartya. (2007), Kekerasan dan Ilusi tentang Identitas (terj.), Jakarta: Marjin Kiri (Penerjemah: Arif Susanto). 36 Lihat:Huntington, Samuel P. (1996), The Clash of Civilizations and the Remaking of th World Order, New York: Simon & Schuster. 37 Sen, Amartya. (2007), op.cit. hlm. 60-62. 38 Sen, Amartya. (2007), op.cit. hlm. 60. 39 Sen, Amartya. (2007), op.cit. hlm. 76. 30 menghancurkan berpotensi terjadi, dan sebenarnya sudah terjadi, di era masyarakat global dan masyarakat jaringan. Identitas tunggal menyebabkan “Sang kekuatan tunggal” dipersatukan dengan “satu identitas” yang menghimpun kekuatannya (sekutu) untuk melawan musuh yang sudah dikerangkeng dengan satu identitas tunggal pula – bisa jadi, Sang kekuatan tunggal menciptakan musuh baru setelah kehancuran komunisme, di mana menggunakan para intelektualnya sebagai pembenaran atas identitas tunggal tersebut. Kritik serupa pun dilontarkan dengan tegas oleh Francis Fukuyama (2006) dalam sebuah jurnal yang berjudul “Identity, Immigration & Democracy”40. Sama seperti Sen (2007), Fukuyama (2006) sebenarnya mengkritik keangkuhan Barat terhadap dunia Islam. Fukuyama melihat bagaimana identitas kaum migran Muslim di Eropa dan Amerika Utara (Barat) yang memarjinalkan imigran Muslim dengan identitas ke-Islamannya, dan ini sangat bertolak belakang dengan demokrasi atau pun asasasas kemanusiaan yang didengungkan oleh Barat ke seluruh penjuru dunia. Pemarjinalan ini tidak terlepas dari ketakutan Barat atas potensi radikalisme dari imigran Muslim di negaranya. Lalu, mengapa mereka menjadi radikal? Mereka menjadi radikal karena mereka dipinggirkan atas nama identitas ke-Islam-annya. Fukuyama dengan tegas menyatakan bahwa modernisasi dan demokratisasi bukan penyelesaian utama atas radikalisme Islam yang ditakuti oleh dunia Barat41. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa gerakan radikal ini merupakan bentuk dari identitas perlawanan (resistance identity) dan identitas proyek (project identity) dalam politik identitas modern. Menurut Fukuyama (2006), radikalisme ini turut disebabkan oleh adanya kekosongan identitas dari generasi ketiga imigran Muslim di Barat yang diisi oleh jihadisme kontemporer. Tidak dapat disangkal lagi, bahwa pengidentitasan tunggal seperti yang dikemukakan oleh Huntington (1996) menyebabkan kemarginalan identitas imigran Muslim ini, seolah-olah imigran Muslim ini adalah musuh nyata yang harus diwaspadai di dalam negara mereka 40 Fukuyama, Francis. (2006), „Identity, Immigration & Democracy‟, Journal of Democracy, Volume 17, Number 2. 41 Fukuyama, Francis. (2006), op.cit. hlm.12: “… the problem of jihadist terrorism will not be solved by bringing modernization and democracy to the Middle East.” 31 (Barat) – yang sebenarnya sebagian dari imigran Muslim ini sudah menjadi bagian dari warga negara di dunia Barat. Sebenarnya kritik atas Identitas (tunggal) yang dilontarkan oleh Sen dan Fukuyama merupakan kritik tentang Identitas atas perspektif Barat. Barat yang memiliki sedikit pengetahuan tentang kebudayaan Timur – sebuah kebudayaan yang sama adiluhung-nya dengan Barat, dan lebih tua dari Barat – dengan kekuasaannya yang mendominasi dunia mencoba menyempitkan kebudayaan Timur ke dalam satu identitas tunggal. Seperti yang menjadi pemikiran dan keyakinan orientalis Edward Said (1979 & 2005)42 bahwa identitas suatu individu atau suatu bangsa tidak bisa dimampatkan, digeneralis, atau disimplifikasikan menjadi “satu dan satusatunya Identitas”. Sejarah yang merentang panjang di belakangnya sesungguhnya mustahil hanya bergerak di satu garis lurus, pasti ada pelbagai macam pengaruh yang saling bercampur aduk dalam merumuskan jatidiri yang terbentuk sekarang43. Singkatnya, Said ingin mengatakan bahwa identitas tidak bisa diabsolutkan secara esensialis – seperti yang dilakukan oleh Barat terhadap Timur. Baik Edward Said maupun Frantz Fanon (yang karya-karyanya berpengaruh besar atas studi pascakolonial, termasuk Edward Said sendiri), sama-sama (bertujuan) menggugat Eropa yang telah menyekat-nyekat manusia ke dalam hirarki ras yang mereduksi dan mendehumanisasikan kaum hamba ke bawah cara pandang ilmiah maupun kehendak kaum penguasa44. Salah satu contohnya adalah bagaimana Pemerintah Kolonial Inggris mengkonstruksikan masyarakat India ke dalam satu hirarki masyarakat yang statis berdasarkan sistem kasta. Sebuah konstruksi identitas yang dilakukan pemerintah kolonial bersama-sama dengan para orientalis dan Brahmana India yang bisa menikmati keuntungan dari pengkonstruksian ini oleh pemerintah kolonial. Ironisnya, apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Inggris diadopsi oleh Pemerintah Kolonial Belanda dalam mengkonstruksikan identitas masyarakat Bali di tahun 1920-an berdasarkan model kasta yang 42 Said, Edward. (1979), Orientalism, New York: Vintage Books. Said, Edward. (2005), Bukan Eropa:Freud dan Politik Identitas Timur Tengah (terj), Jakarta: Marjin Kiri (penerjemah: L.P. Hok). 43 Said, Edward. (2005), op.cit. hlm.vi. 44 Said, Edward. (2005), op.cit. hlm. 16. 32 diberlakukan oleh Pemerintah Kolonial Inggris terhadap masyarakat India – di Bali, model kasta tersebut menjadi Sistem Wangsa: Triwangsa dan Jabawangsa. Dengan beranggapan bahwa Hindu di Bali sama dengan Hindu di India – karena India dianggap sebagai pusat dari perkembangan dan penyebaran agama Hindu di Nusantara. Akibatnya, seperti yang dikatakan oleh Said dan Fanon adalah terjadi “pereduksian dan pendehumanisasikan kaum hamba”. Di India, kaum hambanya adalah kasta sudra dan paria (out of caste, tidak memiliki kasta), dan di Bali, adalah Jabawangsa atau sudrawangsa. Ironis, untuk kasus di Indonesia, gaya kolonial ini masih dipraktekkan oleh pemerintah Republik Indonesia – yang merupakan pemerintahan di masa pasca kolonial – ketika mengharuskan kepercayaan masyarakat Bali – Hindu Bali – agar dikonversikan menjadi Agama Resmi oleh pemerintahan Orde Lama45. Pemerintah Orde Lama yang diwakili Kementerian Agama dengan otoritasnya mengklasifikasikan kepercayaan Indonesia menjadi: Orang yang ber-Agama dan Orang yang belum ber-Agama. Geertz (1974 dan 1992)46 menyebutnya sebagai “Internal Convertion” – masyarakat Bali terpaksa meng-Hindu-kan kepercayaan Hindu-Bali-nya menjadi “Hindu resmi” berdasarkan versi pemerintah. Geertz dengan internal convertion – bisa diterjemahkan sebagai rasionalisasi agama – sebenarnya mengkritik dominasi Weberian dalam mengklasifikasikan agama-agama. Max Weber – dengan karya besarnya yang fenomenal The Protestant Ethics and The Spirit of Capitalism47 – telah menginspirasi para pengikutnya dan para orientalis untuk merasionalisasikan “agama-agama” lain di dunia – yang disebutnya sebagai agama tradisional (kurang rasional) – khususnya ketika Weber (hampir) berhasil merasionalisasikan agama besar dari Timur – Hindu dan Budha – sama seperti yang dilakukannya pada kaum protestan 45 Ulasan ringkasnya dapat dilihat pada Bab Lima disertasi ini di sub-bab Aktor. Geertz, Clifford. (1974), The Interpretation of Cultures: Selected Essays, London: Hutchinson & CO Publisher. Edisi terjemahan: Geertz, Clifford. (1992), Tafsir Kebudayaan, Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 47 Lihat: Weber, Max. (1968), The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism (terj.), New York: Charles Scribner‟s Sons (dialih-bahasakan oleh Talcott Parson dari Bahasa Jerman ke Inggris). 46 33 di Amerika dalam karya berikutnya yang berjudul “The Religion of India: The Sociology of Hinduism and Budhism48”. Seperti yang dikritik oleh Edward Said, Amartya Sen, dan Geertz dengan kasus masyarakat Bali, cara Barat memandang Timur ini yang menjadi pokok kritik mereka, bagaimana para orientalis mengklasifikasikan masyarakat di luar Barat, seolah-olah mereka (Barat) lebih tahu dan pantas mengklasikasikan Timur berdasarkan pengetahuan rasional yang dimilikinya. Diskusi singkat tentang Identitas dari beberapa penulis di atas ditujukan untuk memperkaya pemahaman tentang Identitas, khususnya bagaimana proses pembentukan atau konstruksi sebuah Identitas. Ada berbagai sudut pandang (basis teori) yang digunakan para penulis untuk mengkonstruksikan Identitas. Dari beberapa penulis tersebut, pemikiran Castells dipilih untuk mengkaji proses pembentukan identitas. Dua poin utama dari pemikiran Castells yang akan digunakan untuk mengkaji proses pembentukan identitas adalah tiga bentuk bangunan identitas (legitimizing, resistance, dan project identity) dan aktor sebagai pengkonstruksi identitas. Seperti yang telah dijelaskan di Bagian Pendahuluan, pola hubungan pusatsatelit menjadi sebuah kerangka proses pembentukan identitas. Pusat dan satelit merupakan aktor pengkonstruksi identitas. Tidak hanya pusat yang menjadi aktor yang melegitimasikan identitas satelit menjadi identitas yang sahih (legitimizing identity), tetapi juga satelit sebagai aktor yang mengkonstruksikan identitasnya dengan membentuk resitance dan project identity. Kebalian Jika diskusi di atas – sebagai sebuah tinjauan literatur tentang Identitas – lebih ke aras abstrak, maka di bagian ini diskusinya lebih difokuskan atau lebih mengena ke objek penelitian, yaitu Bali. Seperti yang telah diketahui bahwa kajian atau literatur mengenai Bali telah banyak ditulis oleh para peneliti asing dan lokal. Namun, literatur 48 Lihat: Weber, Max. (1958), The Religion of India: The Sociology of Hinduism and Buddhism (terj.), USA (Glencoe, Illinois): The Free Press (dialih-bahasakan dan dieditori oleh Hans H. Gerth dan Don Martindale). 34 mengenai Bali di luar Bali jumlahnya masih sedikit49, terutama Bali di Lampung seperti yang menjadi objek penelitian ini. Oleh karena itu, dua tema yang dirampatkan dalam sub-bab tinjauan literatur ini adalah Bali di luar Bali dan (sejarah) pengkonstruksian identitas Bali. Pembahasannya akan disajikan secara singkat, karena selain terlalu jauh dengan konteks penelitian Bali di Lampung, literatur ini sebenarnya turut disertakan pada pembahasan isi (bab-bab empirik) dalam disertasi ini (memiliki keterkaitan dengan data empirik pada konteks tertentu, terutama karena tema ini terkait dengan sejarah). Bali di luar Bali. Jika ada Bali di luar Bali, maka ini disebabkan adanya proses migrasi atau lebih tepatnya disebut transmigrasi. Namun, pada bagian ini penulis tidak membahas transmigrasi, karena tema transmigrasi akan dibahas di Bab Tiga (termasuk menggunakan beberapa literatur penunjang). Tanpa memungkiri kenyataan bahwa literatur Bali di luar Bali (sangat) terbatas, yang ada dan akan digunakan oleh penulis, sebenarnya tetap berada pada tema transmigrasi orang Bali yang menyebabkan mereka berada di luar Bali. Untuk itu ada tiga literatur – berdasarkan hasil penelitian – yang akan penulis gunakan untuk membahas secara singkat Bali di luar Bali, yaitu karya Gloria Davis (1976)50, A. A. Bagus Wirawan (2008)51, dan Brian A. Hoey (2003)52. Meskipun ketiga 49 Seandainya ada, itu pun dalam bentuk tidak dipublikasikan, dan belum terjangkau oleh penulis karena hambatan teknis, terutama pendanaan dan akses ke sumber informasi. 50 Davis, Gloria. (1976). “Parigi: A Social History at the Balinese Movement to Central Sulawesi 1907-1974”, Disertasi Doktor Stanford University. Karya Davis ini biasanya menjadi rujukan bagi peneliti sejarah bertransmigrasinya orang Bali dan orang Bali setelah berada di luar Bali, khususnya orang Bali yang berada di Sulawesi. 51 Wirawan, A. A. Bagus. (2008), „Sejarah Sosial Migran-Transmigran Bali di Sumbawa, 1952-1997‟, Yogyakarta: JANTRA (Jurnal Sosial dan Sejarah) Vol. III, No.6 Desember 2008. 52 Hoey, Brian A., „Nationalism in Indonesia: Building Imagined and Intentional Communities Through Transmigration‟, Ethonology, Spring 2003, Vol. 42 Issue 2, P 109, 18 p, 1 bw; (AN 10317586). 35 literatur ini berada pada satu kerangka besar tema “transmigrasi”, namun ketiganya sama-sama membahas orang Bali yang berada di luar Bali. Davis (1976) dan Hoey (2003) mengambil kasus orang Bali di Sulawesi Tengah, sedangkan Wirawan (2008) mengambil kasus orang Bali di Sumbawa. Uraian yang bersifat sejarah lebih ditonjolkan oleh Davis (1976) yang menguraikan dengan ringkas dan bernas sejarah perpindahan (transmigrasi) orang Bali ke Parigi (Sulawesi Tengah) dalam disertasi doktoralnya dan Wirawan (2008) mengenai sejarah transmigrasi orang Bali ke Sumbawa dalam sebuah jurnal nasional. Hoey (2003) meskipun tulisannya dalam tema besar “nasionalisme di Indonesia terkait dengan bangunan komunitas reka-bayang dan terencana melalui transmigrasi, objek penelitian yang diambil adalah transmigran Bali di Sulawesi. Apa yang menarik dari tulisan ketiganya dan relevan dengan penelitian penulis? Hal yang menarik dari ketiganya adalah bahwa orang Bali yang telah berada di luar Bali melalui proses transmigrasi berhasil menghadirkan kosmos Bali – kebudayaan Bali – ke daerah barunya – meskipun harus melalui waktu dan proses yang panjang agar sebisa mungkin kosmos Bali tersebut benar-benar sama dengan yang ada di Bali (dan sesungguhnya tidak bisa menjadi sama seratus persen seperti di Bali). Jadi, orang Bali yang pindah ke luar Bali – dalam kasus ini di Sulawesi dan Sumbawa – turut memindahkan (menyertakan) identitas kebalian mereka. Identitas kebalian sangat melekat pada individu orang Bali – dalam kasus ini transmigran yang berada di Sulawesi dan Sumbawa – dan mereka wajib untuk menghadirkan kosmosnya di daerah tersebut meskipun masih dalam bentuk yang sangat sederhana. Tentu, dalam kasus orang Bali di Sulawesi (dan Sumbawa), Bali yang dimaksudkan adalah Bali Hindu. Orang Bali yang beragama nasrani (umumnya berasal dari Bali Utara, Jembarana) yang turut pindah ke Sulawesi sebenarnya tetap membawa identitas Balinya, tetapi hanya sebagai orang yang lahir di Bali atau ex-Bali (bukan Bali yang sesungguhnya seperti Bali Hindu), bukan identitas kebalian yang mencerminkan kebudayaan Bali itu sendiri. Bagi orang Bali yang sudah menjadi satu dengan Hindu-nya (Bali Hindu), mereka (orang Bali) yang 36 sudah mengonversikan kepercayaan leluhurnya (dari Hindu Bali ke “agama resmi”), maka mereka dianggap sudah bukan Bali lagi53. Identitas Bali yang terkonstruksi. Untuk kasus di Indonesia, Bali merupakan (salah satu) contoh kasus bagaimana identitas suatu masyarakat dikonstruksikan oleh sebuah otoritas (kekuasaan, power). Bagaimana tidak? Bali yang di masa kerajaan menjadi sebuah pulau yang terisolir pasca jatuhnya Kerajaan Hindu di Jawa, dan sebuah pulau yang selalu dipenuhi dengan peperangan sebelum pemerintah kolonial menginvasi Bali di akhir abad ke-19 dan berhasil menguasainya di permulaan abad ke-20, “tiba-tiba” menjadi sebuah pulau yang dicitrakan oleh pemerintah kolonial sebagai paradise – surga dunia – dan living museum (serta pencitraan keeksotikan dan keindahaan yang lain untuk Bali). Sebuah pencitraan yang sebenarnya bertolak-belakang dengan penilaian para pejabat kolonial (Belanda, dan Inggris untuk waktu yang singkat, serta pendatang / pedagang asing) sebelum menginvasi dan menguasai Bali atas pulau ini sebagai sebuah tempat yang penuh kebrutalan. Selain kondisi di pulau ini yang selalu diwarnai dengan peperangan antar kerajaan, Bali dikenal sebagai pengekspor budak terbesar di wilayah Nusantara di masa pemerintahan kolonial Belanda, serta praktek “pembakaran janda” masih dilakukan. Bagaimana sebuah power – yang dalam kasus ini adalah pemerintah yang berkuasa dengan dukungan pemikiran dari para intelektual orientalis Barat – berhasil mendongkrak citra Bali sebagai paradise (dapat dikatakan, penyitraan tersebut masih melekat sampai saat ini) yang menjadi perhatian banyak peneliti (asing) atas pencitraan identitas Bali yang terkonstruksi. Salah satunya adalah Adrian Vickers (1996) melalui bukunya yang terkenal “Bali: A Paradise Created”54. Melalui bukunya tersebut, Vickes 53 Mengutip Geertz (1992, edisi terjemahan) dalam Tafsir Kebudayaan, hlm. 137: “Menjadi entah Kristen atau Muslim, dalam mata mereka, sama dengan berhenti menjadi orang Bali, dan memang seseorang individu yang langka yang bertobat masih dianggap, malah oleh kebanyakan orang yang toleran dan yang terpelajar, teleh meninggalkan tidak hanya agama Bali melainkan Bali, dan barangkali dianggap gila.” 37 mengulas bagaimana penyitraan Bali sebagai paradise dikonstruksikan – pertama kali – oleh pemerintah kolonial Belanda setelah berhasil menguasai Bali di awal abad ke-20 (sekitar tahun 1908) melalui sebuah invasi militer berdarah. Ada kekontrasan yang terjadi ketika pencitraan tersebut berhasil dikontruksikan seolah-olah adalah Bali yang sesungguhnya, seperti yang ditulis oleh Vickers (1996): “The nineteenth-century sailor who was challenged in th market of north Bali bya kriswielding warriors, and the twenttieth-century tourist who watched astounding dances in the Bali Beach Hotel both experienced something of the real Bali.” 55 Selama tahun 1920-an dan 1930-an penyitraan atas Bali mulai ditancapkan oleh pemerintah kolonial, dan tahun 1950-an – pasca-kolonial – penyitraan tersebut sudah menjadi tetap (paten) dan melekat pada masyarakat Bali sebagai objek dari penyitraan tersebut. Tahun 1920-an adalah permulaan proyek Balinisasi atau Baliseering oleh pemerintah kolonial, dan permulaan pengontruksian identitas atas Bali. Melalui proyek Balinisasi tersebut pemerintah kolonial ingin mengembalikan Bali seperti sedia kala – menjadi Bali seperti di masa kerajaan sebelum dihancurkan oleh invasi Belanda. Dengan kata lain, mentradisionalkan Bali seperti aslinya. Melalui proyek Balinisasi juga, pihak Belanda menginginkan agar masyarakat Bali secara mandiri dan otonom bisa terus mempertahankan dan melestarikan identitas kebaliannya – sebuah tindakan yang ceroboh karena di sisi yang lain Belanda telah menghancurkan tatanan sosial masyarakat Bali pasca invasi militer bedarahnya dan menunjuk bangsawan-bangsawan yang mau tunduk kepada Belanda sebagai punggawa kembalinya Bali ke tatanan aslinya, dan ini telah menimbulkan permasalahan sosial dan politik di 54 Vickers, Adrian. (1996), Bali: A Paradise Created, Singapore: Periplus Edition. 55 Vickers, Adrian. (1996), op.cit. hlm. 4-5. Terjemahan bebasnya oleh penulis: “Abad ke-19 pelaut (pedagang) dihadang (ditantang) dalam sebuah pasar di Bali utara oleh pasukan berkeris, dan abad ke-20 wisatawan disuguhkan tarian yang memukau di Hotel Bali Beach, keduanya menunjukkan (pengalaman) sesuatu yang riil (nyata) dari Bali.” 38 dalam masyarakat Bali, seperti yang diungkapkan Robinson (1995) 56 dan Schulte Nordholt (2009) 57. Salah satu pertimbangan utama pihak Belanda waktu itu adalah fakta Bali sebagai satu-satunya wilayah (pulau) Hindu di tengah dominasi Islam di kepulauan Nusantara. Bali merupakan satusatunya wilayah Hindu yang masih bertahan, dan ini merupakan warisan dari Kerajaan Hindu Jawa yang harus dipertahankan dan dilestarikan eksistensinya dari ancaman (kegiatan misioner) Islam dan Kristen58. Di samping itu, dengan mentradisionalkan Bali dengan proyek Balinisasi dan melibatkan orang Bali sendiri (elit-elit, atau bangsawan pilihan Belanda) maka, selain melindungi Bali dari kedua ancaman tersebut, juga yang terpenting bagi Belanda adalah melindungi Bali (sebagai bagian dari wilayah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda) dari gerakan-gerakan nasionalis yang sudah berkembang luas di Hindia Belanda, khususnya Jawa yang sangat dekat dengan Bali secara geografis. Pertimbangan utama berikutnya adalah ekonomi – (hanya) melalui sektor pariwisata Bali bisa memperkokoh perekonomian, karena pulau yang kecil tidak memiliki sumber daya yang mumpuni untuk kegiatan perdagangan hasil bumi, kecuali keeksotisan Bali (di masa kerajaan mengandalkan perdagangan budak), dan pemerintah kolonial bisa mengambil keuntungan melalui sektor pariwisata ini. Karenanya, identitas Bali harus dikontruksikan ulang, dari citra yang “brutal” menjadi “paradise” agar bisa mendongkrak industri pariwisata di Bali59. 56 Lihat: Robinson, Geoffrey. (1995), The Dark Side of Paradise: Political Violence in Bali, Ithaca and London: Cornell University Press. Edisi terjemahan: Robinson, Geoffrey. (2006), Sisi Gelap Pulau Dewata: Sejarah Kekerasan Politik (terj.), Yogyakarta: LkiS (dialih-bahasakan oleh Arif B. Prasetyo). 57 Lihat: Schulte Nordholt, Henk. (2009), The Spell of Power: Sejarah Politik Bali 1650-1940, Denpasar: Pustaka Larasan dan KITLV-Jakarta. 58 Lihat: Robinson (1995), op.cit, dan Vickers (1996), op.cit. 59 Tahun 1908 Bali sudah mulai dikuasai utuh oleh Belanda, dan tahun 1914 Bali sudah dijadikan salah satu daerah tujuan pariwista yang diikuti dengan pengontrolan keamanan oleh pasukan pemerintah kolonial. Tidak sampai tahun 1924 pariwisata Bali sudah dikembangkan setelah perusahaan pelayaran Belanda rute Singaraja dengan Batavia dan Makassar. Akhirnya, di tahun 1928 “Bali Hotel” dibangun di Denpasar untuk menampung wisatawan yang akan berkunjung ke Bali. Lihat: Picard, Michel. (1997), “Cultural Tourism, Nation-Building, and 39 Berdasarkan Vickers (1996) dan Picard (1997, 1999, 2005, 2008) , penulis mengklasifikasikan setidaknya dua alasan mendasar mengapa identitas Bali dikatakan sebagai sebuah identitas yang dikontruksikan, di antaranya: (1) ada aktor atau agen, dalam kasus ini adalah pihak yang memiliki kekuasaan (power), yang mengontruksikan identitas Bali dengan otoritasnya. Bila mengacu pada Castells (2002) pengonstruksian (salah bentuk pengonstruksian identitas) identitas ini dapat dikategorikan sebagai legitimizing identity61 (identitas yang sahih); (2) kontradiksi fakta sejarah antara citra paradise yang ditanamkan (identitas yang dikontruksikan) oleh otoritas dengan realitas yang ada, seperti: surga dunia versus brutalisme62. Ini yang menjadi pertanyaan 60 Regional Culture: The Making of a Balinese Identity”, dalam Picard, Michel & Wood, Robert E. (Ed.), Tourism, Ethnicity, and the State in Asian and Pacific Societies, USA: University of Hawai‟I Press Honolulu. 60 Picard, Michel. (1997), op.cit. . Picard, Michel. (1999), “The Discourse of Kebalian: Transcultural Constructions of Balinese Identity”, dalam Rubinstein, Raechelle & Connor, Linda H. (Ed.), Staying Local in the Global Village: Bali in the Twentieth Century, Honolulu-USA: University of Hawai‟i Press. Picard, Michel. (2005), “Otonomi Daerah in Bali: The Call for Special Outonomy Status in the Name of Kebalian”, dalam Erb, Maribeth; Sulistiyanto, Priyambudi; & Faucher, Carole. (Ed.), Regionalism in Post-Suharto Indonesia, USA and Canada: RoutledgeCurzon. Picard, Michel. (2008), „Balinese Identity as Tourist Attraction: From „Cultural Tourism‟ (pariwisata budaya) to „Bali Erect‟ (ajeg Bali)‟, SAGE PUBLICATIONS: Tourist Studies 2008; 8; 155. 61 Mengutip Castells (2002), op.cit., hlm. 8: “Legitimizing identity: introduced by the dominant institution of society to extend and rationalize their domination vis a vis social actors, a theme that is at the heart of Sennett‟s theory of authority and domination, but also fits with various theories of nationalism.” 62 Untuk melihat kontradiksi sejarah ini – khususnya tragedi-tragedi sejarah atau “sisi gelap” Bali – yang kontras dengan citra “paradise” secara detail dan mendalam baca: Robinson (1995), op.cit. dan Schulte Nordholt (2009), op.cit. Uraian detail Robinson mengambil waktu sejarah mulai dari masa kolonial sampai pasca kolonial (berdirinya Orde Baru), sedangkan Schulte Nordholt dari masa 40 mendasar kedua penulis ini, apakah itu paradise yang sesungguhnya. Kontradiksi ini yang memperkuat tesis mereka bahwa identitas Bali merupakan identitas yang dikonstruksikan, atau dalam bahasanya Vickers (1996) a paradise created. Lalu, identitas apa yang dikontruksikan atas Bali? Identitas yang dikonstruksikan tersebut adalah identitas kebalian. Atau, oleh Picard (1997, 1999, 2005, 2008) bisa disebut atau diartikan sebagai kebudayaan Bali atau gabungan dari elemen penting kebudayaan Bali seperti kepercayaan, adat atau tradisi dan kesenian. Kebudayaan Bali atau kebalian ini yang kemudian dijadikan sebagai modal utama bagi industri pariwisata di Bali, dalam bahasanya Picard disebut pariwisata budaya. Ironisnya, identitas kebalian tersebut mengalami paradoks yang menyebabkan menghangatnya wacana Ajeg Bali di Bali saat ini. Identitas kebalian menjadi modal utama bagi industri pariwisata Bali – yang menyebabkan mereka harus terbuka karena ketergantungan ekonomi Bali dari sektor industri pariwisata – diperhadapkan dengan tergerusnya kebudayaan Bali63. Situasi paradoksal dan dilematis ini yang disebutkan oleh Schulte Nordholt (2007) bagaimana menjadikan Bali sebagai sebuah “benteng terbuka” – melindungi kebudayaan Bali tanpa menutup diri terhadap dunia luar. Untuk konteks Indonesia, mengapa Identitas menjadi penting? Identitas menjadi penting di Indonesia – terutama pasca Suharto – dikarenakan berkembangnya fenomena politik identitas – selain masalah identitas ke-Indonesia-an (kebangsaan, nasionalisme) yang masih dipertanyakan seperti yang dikritik oleh Benedict Anderson untuk kerajaan sampai kolonial mulai melakukan ekspansi dan invasi sampai berhasil menguasai Bali (sebelum Jepang menguasai Bali). 63 Lihat: Picard (2008), op.cit. dan Schulte Nordholt, Henk. (2007), Bali: An Open Fortress 1995-2005 (Regional Autonomy, Electoral Democracy and Entrenched Identities, Singapore: NUS Press. Edisi terjemahan: Schulte Nordholt, Henk. (2007), Bali: Benteng Terbuka 1995-2005 (Otonomi Daerah, Demokrasi Elektoral, dan Identitas-Identitas Defensif) (terj.), Denpasar: Pustaka Larasan dan KITLV-Jakarta. 41 Indonesia pasca kolonial64. Identitas bisa menjadi masalah dan sumber permasalahan dikarenakan adanya kesolidaritasan kelompok berdasarkan identitasnya. Dengan kata lain, ada penguatan identitas, baik penguatan identitas berbasiskan agama, etnis, golongan atau pun kepentingan. Permasalahan ini menjadi pelik dan mengganggu proses pembangunan ketika ada di antara kelompok yang mengalami penguatan identitas bertemu dalam satu arena yang sama, konflik atau kekerasan bisa dan berpotensi terjadi – seperti yang dikemukakan Stuart Hall (2000), dalam konteks globalisasi, bahwa globalisasi menyebabkan penguatan identitas lokal atau menciptakan identitas-identitas baru, dan ini disebabkan oleh keterancaman atas dominasi identitas etnik dominan65. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil penelitian Gerry van Klinken (2007)66 yang menggambarkan kekerasan yang terjadi di Indonesia (terutama kekerasan berbasiskan identitas etnis dan agama) di saat Indonesia mulai memasuki masa demokrasi modern pasca Suharto – Van Klinken menyebutkannya dengan “small town wars”. Pemaparan contoh kasus seperti perang sipil yang terjadi pada kasus di Kalimantan dan Ambon, cukup jelas bahwa konflik tersebut menggunakan Identitas etnis dan agama sebagai akar konflik. Jika tidak ada kesolidan kelompok berbasiskan identitas etnis dan agama, maka konflik (hampir) tidak dimungkinkan terjadi. Penguatan identitas kelompok-kelompok berbasis massa ini yang digunakan sebagai alat propaganda pihak tertentu untuk mengadu domba, dengan menjadikan Identitas sebagai masalah utamanya. Pembahasan yang lebih menyeluruh tentang fenomena politik identitas di Indonesia pasca Suharto juga diulas secara komprehensif dalam buku “Politik Lokal di Indonesia” yang 64 Anderson, B. R. O. G. (1991), Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London: Verso. “Imagined Communities” dalam Indonesia bisa diartikan sebagai komunitas terbayang atau komunitas rekabayang. 65 Hall, Stuart (2000), “The Question of Cultural Identity”, dalam Nash, Kate. (Ed.), Readings in Contemporary Political Sociology, Oxford: Blackwell. Hlm.117. 66 Van Klinken, Gerry. (2007), Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small Town Wars, London and New York: Roudledge. 42 dieditori oleh Gerry van Klinken dan Henk Schulte Nordholt (2007)67. Dalam buku tersebut, yang diulas secara komprehensif dari berbagai kasus politik lokal di Indonesia, nuansa atau fenomena politik identitas pasca Suharto – ketika demokrasi diartikan sebagai kebebasan berpendapat dan bereskpresi seenaknya – menjadi warna dalam politik lokal di Indonesia. 67 Schulte Nordholt, Henk & Van Klinken, Gerry. (2007), Politik Lokal di Indonesia, Jakarta: Buku Obor & KITLV Jakarta. 43 44