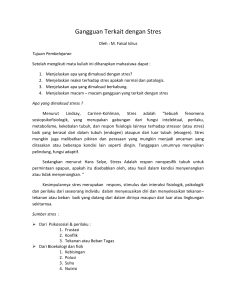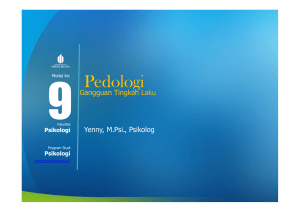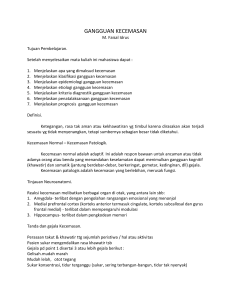gangguan stres pascatrauma dan gangguan stres akut
advertisement

GANGGUAN STRES PASCATRAUMA DAN GANGGUAN STRES AKUT Gangguan stres pascatrauma (posttraumatic stress disorder- PTSD) adalah suatu sindrom yang timbul setelah seseorang melihat terlibat di dalam, atau mendengar stresor traumatik yang ekstrem. Seseorang bereaksi terhadap pengalaman tersebut dengan rasa takut dan tidak berdaya, secara menetap menghidupkan kembali peristiwa tersebut, dan mencoba menghindari mengingat hal itu. Untuk menegakkan diagnosis, gejala harus memengaruhi area penting kehidupan secara signifikan, seperti keluarga dan pekerjaan. Edisi keempat revisi Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM-IV-TR) mendefinisikan gangguan yang serupa dengan PTSD sebagai gangguan stres akut, yang terjadi lebih dini dari PTSD (dalam 4 minggu setelah peristiwa) dan membaik dalam 2 hari hingga 4 minggu. Jika gejala bertahan setelah waktu tersebut, diagnosis PTSD diperlukan. EPIDEMIOLOGI Prevalensi seumur hidup PTSD diperkirakan sekitar 8 persen populasi umum walaupun tambahan 5 hingga 15 persen dapat mengalami bentuk subklinis gangguan ini. Di antara kelompok risiko tinggi yang anggotanya mengalami peristiwa traumatik, angka prevalensi seumur hidupnya berkisar 5 hingga 75 persen. Sekitar 30 persen veteran Vietnam mengalami PTSD dan tambahan 25 persen mengalami bentuk subklinis gangguan tersebut. Prevalensi seumur hidup pada perempuan berkisar sekitar 10 hingga 12 persen dan 5 hingga 6 persen pada laki-laki. Walaupun PTSD dapat timbul pada usia berapapun, gangguan ini paling prevalen pada dewasa muda karena mereka cenderung lebih terpajan dengan situasi penginduksi. Anak juga dapat mengalami gangguan ini. Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan tipe trauma yang memajankan mereka dan kecenderungan untuk mengalami PTSD. Prevalensi seumur hidup secara bermakna lebih tinggi pada perempuan dan proporsi perempuan yang terus mengalami gangguan ini lebih tinggi. Berdasarkan sejarah, trauma laki-laki biasanya berupa pengalaman berperang dan trauma perempuan paling lazim adalah kekerasan atau perkosaan. Gangguan ini lebih cenderung terjadi pada orang lajang, bercerai, janda, menarik diri secara sosial, atau tingkat sosioekonomi yang rendah. Meskipun demikian, faktor risiko paling penting gangguan ini adalah keparahan, durasi dan kedekatan pajanan seseorang dengan trauma yang sebenarnya. Tampaknya terdapat pola familial untuk gangguan ini dan kerabat biologis derajat pertama orang dengan riwayat depresi memiliki peningkatan risiko untuk timbulnya PTSD setelah peristiwa traumatik. KOMORBIDITAS Angka komorbiditas tinggi pada pasien dengan PTSD, dengan sekitar dua pertiga memiliki sedikitnya dua gangguan lain. Keadaan komorbid yang lazim mencakup gangguan depresif, gangguan terkait zat, gangguan ansietas lain, dan gangguan bipolar. Gangguan komorbid membuat orang menjadi lebih rentan untuk mengalami PTSD. ETIOLOGI Stresor Stresor yang menyebabkan stres akut dan PTSD cukup hebat untuk memengaruhi hampir setiap orang. Stresor dapat timbul dari pengalaman perang, penyiksaan, bencana alam, penyerangan, perkosaan, dan kecelakaan serius (contohnya di dalam mobil dan gedung terbakar). Meskipun demikian, tidak setiap orang mengalami gangguan ini setelah peristiwa traumatik. Stresornya sendiri tidak cukup menimbulkan gangguan ini. Klinisi harus mempertimbangkan faktor psikososial dan biologis yang sebelumnya ada dan peristiwa yang terjadi sebelum dan setelah trauma. Contohnya, seorang anggota suatu kelompok yang bertahan hidup pada bencana kadang-kadang dapat menangani trauma karena anggota yang lainnya juga mengalami pengalaman yang sama. Arti subjektif suatu stresor pada seseorang juga penting. Contohnya, orang yang selamat dari bencana dapat mengalami rasa bersalah (survivor guilt) yang dapat menjadi predisposisi atau memperberat PTSD. Faktor Risiko Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahkan ketika menghadapi trauma yang hebat, sebagian besar orang tidak mengalami gejala PTSD. National Comobidity Study menemukan bahwa 60 persen laki-laki dan 50 persen perempuan mengalami sejumlah trauma yang signifikan, tetapi prevalensi PTSD yang dilaporkan hanya 6,7 persen. Demikian juga, peristiwa yang mungkin tampak biasa atau kurang dianggap sebagai bencana besar bagi sebagian besar orang dapat menimbulkan PTSD pada sejumlah orang lainnya. Faktor Psikodinamik Model psikoanalitik gangguan ini menghipotesiskan bahwa trauma mengaktifkan kembali konflik psikologis yang sebelumnya tenang, tetapi tidak terselesaikan. Penghidupan kembali trauma masa kanan-kanak menimbulkan regresi dan penggunaan mekanisme defens represi, penyangkalan, reaction formation, dan undoing. Menurut Freud, pemecahan kesadaran terjadi pada pasien yang melaporkan riwayat trauma seksual masa kanak-kanak. Konflik yang sebelumnya telah ada secara simbolis dibangkitkan kembali oleh peristiwa traumatik yang baru. Ego menghidupkan kembali dan dengan demikian mencoba menguasai dan mengurangi ansietas. Orang yang menderita aleksitimia, yaitu ketidak mampuan mengidentifikasi atau memverbalisasikan keadaan perasaan, tidak mampu menenangkan dirinya ketika berada dalam stres. Faktor Perilaku-Kognitif Model kognitif PTSD membuat postulat bahwa orang yang mengalaminya tidak mampu memroses atau merasionalkan trauma yang mencetuskan gangguan ini. Mereka terus mengalami stres dan berupaya menghindari mengalami hal itu dengan teknik penghindaran. Konsisten dengan kemampuan parsial mereka menghadapi peristiwa tersebut secara kognitif, orang tersebut mengalami periode bergantian antara memahami dan memblok peristiwa. Upaya otak untuk memroses jumlah informasi yang banyak yang dicetuskan trauma dianggap menimbulkan periode bergantian antara memahami dan memblok peristiwa. Model perilaku PTSD menekankan adanya dua fase di dalam perkembangannya. Pertama, trauma (stimulus yang tidak dipelajari), yang menimbulkan respons takut, dipasangkan, melalui pembelajaran klasik, dengan stimulus yang dipelajari (pengingat fisik atau mental terhadap trauma, seperti penglihatan, bau, atau suara). Kedua, melalui pembelajaran instrumental, stimulus yang dipelajari mencetuskan respons takut yang bebas dari stimulus asal yang tidak dipelajari, dan orang mengembangkan pola penghindaran terhadap stimulus yang dipelajari maupun stimulus yang tidak dipelajari. Sejumlah orang juga menerima keuntungan sekunder dari dunia luar, umumnya berupa kompensasi keuangan, meningkatnya perhatian atau simpati, pemuasan akan kebutuhan ketergantungan. Keuntungan ini menyokong gangguan dan menetapnya gangguan. Faktor Biologis Teori biologis PTSD berkembang dari studi praklinis para model stres hewan dan dari ukuran variabel biologis dalam populasi klinis dengan gangguan tersebut. Banyak sistem neurotransmiter yang terlibat dalam kedua rangkaian data. Model praklinis ketidakberdayaan yang dipelajari, pembangkitan, dan sensitisasi pada hewan telah menghasilkan teori mengenai reseptor norepinefrin, dopamin, opioid endogen, dan benzodiazepin, serta aksis hipotalamushipofisis-adrenal (HPA). Di dalam populasi klinis, data menyokong hipotesis bahwa sistem noradrenergik dan opiat endogen, seperti aksis HPA, hiperaktif pada sedikitnya sejumlah pasien dengan PTSD. Sistem Noradrenergik. Para tentara dengan gejala mirip PTSD menunjukkan kegugupan, peningkatan tekanan darah dan denyut jantung, palpitasi, berkeringat, rona merah di wajah, dan tremor—yaitu gejala yang berkaitan dengan obat adrenergik. Sejumlah studi menemukan peningkatan konsentrasi epinefrin urin 24 jam pada veteran dengan PTSD dan meningkatnya konsentrasi katekolamin urin pada anak perempuan yang mengalami penyiksaan seksual. Lebih jauh lagi, reseptor β-adrenergik limfosit dan α2 trombosit mengalami downregulation pada PTSD, kemungkinan sebagai respons terhadap konsentrasi katekolamin yang meningkat kronis. Sekitar 30 hingga 40 persen pasien PTSD melaporkan kilas balik setelah pemberian yohimbin (Yocon). Temuan ini adalah bukti kuat perubahan fungsi sistem noradrenergik pada PTSD. Sistem Opioid. Abnormalitas sistem opioid dikesankan dengan adanya penurunan konsentrasi β-endorfin plasma pada PTSD. Veteran perang dengan PTSD menunjukkan respons analgesik yang reversibel dengan nalokson untuk stimulus yang berkaitan dengan perang sehingga meningkatkan kemungkinan hiperregulasi sistem opioid yang serupa dengan hiperregulais pada aksis HPA. Faktor Pelepas Kortikotropin dan Aksis Hipotalamus Hipofisis-Adrenal. Beberapa faktor mengacu pada disfungsi aksis HPA. Sejumlah studi menunjukkan konsentrasi kortisol bebas yang rendah di dalam plasma dan urin pada PTSD. Terdapat peningkatan reseptor glukokortikoid pada limfosit dan tantangan dengan faktor pelepas kortikotropin (CRF) eksogen menunjukkan respons hormon adrenokortikotropin (ACTH) yang tumpul. Lebih lagi, supresi kortisol melalui tantangan dengan dosis rendah deksametason (Decadron) meningkat pada PTSD. Hal ini menunjukkan hiperregulasi aksis HPA pada PTSD. Sejumlah studi juga telah menemukan terjadinya hipersupresi kortisol pada pasien yang terpajan trauma dan mengalami PTSD dibandingkan pasien yang terpajan trauma tetapi tidak mengalami PTSD, sehingga mungkin hipersupresi ini secara spesifik berkaitan dengan PTSD bukan hanya dengan trauma. Secara keseluruhan, hiperregulasi aksis HPA berbeda dengan aktivitas neuroendokrin yang biasanya terlihat selama stres dan pada gangguan lain seperti depresi. Baru-baru ini, peran hipokampus mendapatkan peningkatan perhatian walaupun masalah ini tetap kontroversial. Studi hewan menunjukkan bahwa stres terkait dengan perubahan struktural hipokampus dan studi pada veteran perang dengan PTSD menunjukkan volume rerata yang lebih rendah di regio hipokampus otak. Lebih lagi, peneliti mengajukan bahwa hipokampus bukanlah satu-satunya area otak yang menunjukkan adanya perubahan struktural pada PTSD karena studi mengenai depresi menunjukkan efek serupa di amigdala dan korteks prafrontal. DIAGNOSIS Kriteria diagnosis DSM-IV-TR untuk PTSD merinci bahwa gejala mengalami, menghindari, dan terus terjaga telah ada lebih dari 1 bulan. Untuk pasien yang gejalanya ada, tetapi kurang dari 1 bulan, diagnosis yang sesuai adalah gangguan stres akut. Kriteria diagnostik DSM-IVTR PTSD memungkinkan klinisi merinci apakah gangguan tersebut akut (jika gejala kurang dari 3 bulan) atau kronis (jika gejala telah ada selama 3 bulan atau lebih). DSM-IV-TR juga memungkinkan klinisi merinci bahwa gangguan tersebut dengan awitan yang tertunda jika awitan gejala 6 bulan atau lebih setelah peristiwa yang memberikan stres. GAMBARAN KLINIS Gambaran klinis utama PTSD adalah mengalami kembali suatu peristiwa yang menyakitkan, suatu pola menghindari dan mematikan emosi, serta keadaan terus terjaga yang cukup konstan. Gangguan ini dapat tidak timbul sampai berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun setelah peristiwa tersebut. Pemeriksaan status mental sering mengungkapkan rasa bersalah, penolakan, dan cemoohan. Pasien juga dapat menggambarkan keadaan disodiatif dan serangan panik, serta ilusi dan halusinasi dapat timbul. Uji kognitif dapat menunjukkan bahwa pasien memiliki hendaya memori dan perhatian. Gejala terkait dapat mencakup agresi, kekerasan, kendali impuls yang buruk, depresi, dan gangguan terkait zat. Pasien memiliki peningkatan skor Sc, D, F, dan Ps pada Minnesota Multiphasic Personality Inventory, dan temuan uji Roscharch sering mencakup hal-hal yang agresif dan kasar. Gangguan Stres Pascatrauma pada Anak dan Remaja PTSD terdapat pada anak dan remaja, tetapi sebagian besar studi gangguan ini telah berpusat pada orang dewasa. DSM-IV-TR hanya mengemukakan sedikit mengenai PTSD pada anak yang masih kecil, kecuali dengan menggambarkan gejala seperti mimpi berulang mengenai peristiwa tersebut, mimpi buruk tentang monster, serta timbulnya gejala fisik seperti sakit perut dan sakit kepala. Tingginya angka PTSD belum didokumentasikan pada anak yang terpajan peristiwa yang mengancam jiwa seperti peperangan dan trauma terkait perang lain, penculikan, penyakit berat atau terbakar, transplantasi sumsum tulang, dan sejumlah bencana alam buatan dan manusia. Studi pada korban yang masih muda atau saksi penyerangan kriminal, kekerasan rumah tangga, dan kekerasan masyarakat mengungkapkan morbiditas psikiatri yang tinggi setelah pajanan terhadap kekerasan tersebut. Seperti yang mungkin diperkirakan, prevalensi PTSD lebih tinggi pada anak daripada orang dewasa yang terpajan stresor yang sama. Pada situasi tertentu, hingga 90 persen anak akan mengalami gangguan tersebut. Umumnya, PTSD diremehkan pada anak dan remaja. Faktor risiko anak mencakup faktor demografik (cth., usia, jenis kelamin, status sosioekonomi), peristiwa hidup lain (positif dan negatif), kognisi sosial dan budaya, komorbiditas psikiatri, strategi koping yang diturunkan. Faktor keluarga (cth., psikopatologi dan fungsi orang tua, status perkawinan, dan edukasi) memerankan peran kunci dalam menentukan gejala pada anak. respons orang tua terhadap peristiwa traumatik terutama memengaruhi anak yang masih kecil yang belum benar-benar mengerti sifat trauma atau bahaya yang terkandung. Stresor. Stresor pada anak dapat mendadak, berupa trauma peristiwa tunggal yang mendadak atau trauma kronis atau terus menerus seperti penyiksaan fisik atau seksual. Anak juga menderita akibat pajanan “tidak langsung”—yaitu, kematian atau cedera orang yang dicintai yang tidak disaksikan, seperti pada situasi bencana, perang, atau kekerasan masyarakat. Menghidupkan dan Mengalami Kembali Peristiwa. Anak seperti orang dewasa, mengalami kembali peristiwa traumatik dalam bentuk pikiran atau ingatan, kilas balik, dan mimpi yang mengganggu serta menimbulkan distres. Mimpi buruk pada anak secara khusus dapat terkait dengan tema trauma atau dapat menjadi umum sebagai rasa takut lainnya. Kilas balik terjadi pada anak dan sesama korban remaja maupun dewasa. “Sandiwara traumatik”, suatu bentuk khusus mengalami kembali yang terlihat pada anak yang masih kecil, terdiri atas memerankan berulang trauma atau tema yang terkait trauma di dalam permainan. Anak yang lebih tua dapat menggabungkan aspek trauma ke dalam hidup mereka di dalam suatu proses yang disebut menghidupkan kembali (reenactment). Tindakan khayalan mengenai intervensi atau balas dendam lazim ada; remaja harus dipertimbangkan memiliki peningkatan risiko untuk bertindak impulsif akibat kemarahan dan khayalan balas dendam. Perilaku terkait pada anak dan remaja korban trauma mencakup memainkan peran seksual, penggunaan zat, dan kenakalan remaja. Anak sering menarik diri dan menunjukkan kurangnya minat pada aktivitas yang sebelumnya menyenangkan. Perilaku regresif seperti enuresis atau takut tidur sendiri juga dapat terjadi. Sindrom Perang Teluk Pada Perang Teluk Persia melawan Irak, yang dimulai tahun 1990 dan berakhir pada tahun 1991, sekitar 700.000 tentara Amerika bertugas di kekuatan koalisi. Walaupun angka morbiditas dan mortalitas minimal jika dibandingkan dengan perang sebelumnya, saat mereka kembali, lebih dari 100.000 veteran melaporkan sejumlah besar masalah kesehatan, termasuk iritabilitas, rasa lelah kronis, nafas pendek, nyeri sendi dan otot, sakit kepala migrain, gangguan pencernaan, ruam kulit, rambut rontok, sering lupa, dan sulit berkonsentrasi. Jika digabungkan, gejala-gejala ini disebut sindrom Perang Teluk, tetapi tidak ada agen pemerintah yang mengidentifikasi penyebab gejala ini. Banyak veteran yakin bahwa gangguan mereka disebabkan oleh pajanan terhadap agen biologis dan kimia seperti asap dari sumur minyak yang terbakar dan kandungan tanah atau mustard dan gas saraf lainnya. Departemen Pertahanan Amerika Serikat memahami bahwa hingga 20.000 pasukan yang bertugas di area perang mungkin terpajan senjata kimia, tetapi menyangkal bahwa mereka yang mengeluhjkan sindrom ini menderita akibat pengaruh pajanan kimia. Bukti terbaik menunjukkan bahwa keadaan ini adalah suatu gangguan yang pada sejumlah kasus dapat dicetuskan oleh pajanan terhadap toksin yang tidak diketahui. Satu studi pada hilangnya ingatan menemukan adanya perubahan struktural lobus parietal kanan pada 18 orang laki-laki dengan sindrom Perang Teluk dengan menggunakan magnetic resonance spectroscopy (MRS). Kelainan otak tersebut diketahui berhubungan dengan gejala klinis tertentu. Data baru menunjukkan bahwa kerusakan ganglia basalis dan disfungsi neurotransmiter selanjutnya pada veteran Perang teluk dapat memberikan dasar neurologis sindrom ini. Penyebabnya juga telah dikaitkan dengan stres psikologis akibat berada di daerah perang. Sejumlah studi telah menemukan angka keluhan fisik dan penderitaan psikologis yang lebih tinggi pada veteran yang telah ditugaskan di daerah teluk Persia dibandingkan dengan mereka yang bertugas di Jerman atau Amerika selama perang ini, bahkan setelah mengendalikan efek demografik. Meskipun demikian, hal ini juga dapat disebabkan oleh toksin di daerah tersebut dan bukan hanya karena stres. PTSD (dan gejala terkait) adalah keadaan yang terdokumentasi dengan baik yang terjadi di masa perang. PTSD pertama kali diidentifikasi setelah perang Sipil dan telah dicatat di setiap perang setelah itu, walaupun dengan nama berbeda. Namun, banyak studi pada veteran Perang Teluk menemukan angka PTSD yang lebih rendah daripada mereka yang ditemukan di antara veteran dari perang sebelumnya, yang dapat memberikan dukungan terhadap sindrom terpisah. Meskipun demikian, serupa dengan sejumlah pasien ternyata memiliki gangguan mood dan ansietas yang dapat diobati tetapi tidak didiagnosis karena gejala mereka terutama somatik. Penyiksaan Siksaan fisik yang psikologis yang disengaja terhadap seseorang oleh yang lain dapat memiliki efek yang merusak emosi yang serupa dengan dan mungkin lebih buruk daripada efek yang terlihat akibat perang dan beberapa jenis trauma lain. Seperti yang didefinisikan Perserikatan Bangsa Bangsa, penyiksaan adalah setiap pencederaan secara sengaja berupa sakit mental yang berat atau penderitaan, biasanya melalui perlakuan atau hukuman yang kejam, tanpa perikemanusiaan, atau mempermalukan. Definisi yang luas ini mencakup berbagai bentuk kekerasan interpersonal, dari penyiksaan rumah tangga yang berlangsung lama hingga pembunuhan suatu golongan atau bangsa dalamskala luas. Menurut Amnesty International, penyiksaan lazim terjadi dan tersebar luas di sebagian besar dari 150 negara di seluruh dunia tempat pelanggaran terhadap hak asasi manusia didokumentasikan. Gambaran terkini memperkirakan bahwa di antara 5 dan 35 persen dari 14 juta pengungsi dunia sedikitnya memiliki satu pengalaman penyiksaan; angka ini tidak memperhitungkan akibat kericuhan politik, regional, dan agama terkini di Eropa Timur, Yugoslavia lama, dan Timur Tengah. Penyiksaan berbeda dengan sebagian besar jenis trauma lain karena penyiksaan dilakukan oleh manusia dan secara sengaja. Seseorang yang bekerja untuk dirinya atau untuk otoritas yang lebih tinggi dapat menyiksa orang lain untuk menghukum, meminta ganti rugi, atau memperoleh imformasi dari korban. Metodenya dapat fisik, sontohnya dalam bentuk pemukulan, membakar kulit, kejut listrik, atau membuat asfiksia; maupun psikologis, melalui ancaman, dipermalukan, atau dipaksa melihat orang lain, seringnya orang yang dicintai, disiksa. Satu metode penyiksaan yang khas dan dapat menggabungkan aspek fisik dan psikologis adalah pencucian otak. Walaupun banyak bentuk penyiksaan dapat meninggalkan luka fisik yang sulit hilang yang dapat menjadi pengingat trauma, tampaknya tujuan sebenarnya adalah efek psikologis—penyiksa mencetuskan rasa takut, tidak berdaya, dan akhirnya, kelemahan fisik dan jiwa pada korban. Angka prevalensi PTSD yang dilaporkan di antara orang yang selamat dari penyiksaan adalah sekitar 36 persen, jauh lebih tinggi daripada rerata prevalensi seumur hidup, dan peneliti setuju bahwa keparahan dan durasi PTSD dapat lebih besar ketika stresornya berasal dari manusia. Sejumlah studi juga mengungkapkan komorbiditas penting bersamaan dengan depresi dan gangguan ansietas pada korban penyiksaan. Keluhan psikologis yang lazim lainnya mencakup somatisasi, gejala obsesif kompulsif, kemarahan-permusuhan, gfobia, gagasan paranoid, dan episode psikotik. Metode terapi untuk orang yang selamat dari penyiksaan sama dengan metode terapi untuk gejala dan gangguan pascatrauma lain tetapi klinisi harus sangat sensitif terhadap rangkaian peristiwa hidup penuh tekanan yang dialami korban penyiksaan. Banyak orang selamat yang datang untuk terapi merupakan pengungsi dan menghadapi stresor pascatrauma baru di luar efek penyiksaan, seperti perpisahan dari keluarga, kesulitan mencari pekerjaan, kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan, hambatan bahasa, kesepian, kemiskinan, dan diskriminasi ras. Keyakinan religius, esukasi politik dan komitmen, dukungan sosial yang kuat, serta kesiapan mental terhadap kemungkinan penyiksaan tampak berperan sebagai faktor pelindung timbulnya PTSD dan akibat psikologis lain setelah penyiksaan. Lebih lagi, faktor religius dan budaya yang memengaruhi gaya adaptasi juga dapat memengaruhi respons terapi pada orang yang selamat dari penyiksaan. Pencucian Otak Pencucian otak pertama kali dilakukan oleh Komunis Cina terhadap tawanan Amerika Serikat selama Perang Korea, berupa pembentukan syok budaya yang disengaja. Suatu keadaan isolasi, pengasingan, dan intimidasi dikembangkan untuk mengekspresikan tujuan menyerang kekuatan ego dan menjadikan orang yang dicuci otaknya rentan terhadap peletakan gagasan dan perilaku asing yang biasanya akan mereka tolak. Pencucian otak bertumpu pada pemaksaan fisik dan jiwa. Semua orang rentan terhadap pencucian otak jika mereka terpajan hal tersebut dalam waktu cukup lama, jika mereka sendiri dan tanpa dukungan, dan jika mereka tanpa harapan dapat melarikan diri dari situasi tersebut. Permanen atau tidaknya pengaruh psikologis bergantung pada kekuatan sifat individu dan sistem perawatan jiwa, dalam bentuk pembebasan dari pencucian otak, biasanya diperlukan untuk membantu orang yang telah dicuci otaknya untuk menyesuaikan kembali setelah pengalaman pencucian otak dengan lingkungannya yang biasa. Terapi dukungan ditawarkan dengan penekanan pada edukasi kembali, pemulihan kekuatan ego yang ada sebelum trauma, dan pengurangan rasa bersalah dan depresi yang merupakan sisa pengalaman menakutkan dan hilangnya kepercayaan serta kebingungan identitas akibat trauma tersebut. Terorisme Aktivitas teroris pada tanggal 11 September 2001, saat dihancurkan dan dirusaknya World Trade Center di kota New York dan Pentagon di Washington DC, mengakibatkan lebih dari 3.500 jiwa meninggal dan cedara, membuat trauma suatu negara yang banyak warganya memerlukan intervensi terapeutik. Sebuah survei pada lebih dari 500 orang dewasa Amerika yang dilakukan kurang dari 1 bulan setelah peristiwa untuk mengkaji reaksi mereka serta reaksi anak mereka terhadap serangan teroris menemukan hal berikut ini: Empatpuluh lima persen orang dewasa melaporkan satu atau lebih gejala stres yang mendasar, seperti pengingatan kembali peristiwa yang membuat penderitaan tersebut, insomnia, mimpi buruk, rasa takut, dan iritabilitas, disamping gejala lain. Sembilanpuluh persen dari mereka yang diwawancarai melaporkan derajat gejala ringan. Kerentanan terhadap gejala ditemukan pada perempuan, bukan kulit putih, memiliki penyakit psikologis sebelumnya, dan dekat dengan tempat bencana. Sebagian besar orang dewasa berespons terhadap serangan dengan membicarakan perasaan mereka dengan orang lain, mendatangi tempat pelayanan religius, dan mendonasikan hadiah amal. Lebih dari 80 persen orang tua melaporkan bahwa anak mereka memiliki satu atau lebih gejala. Satu temuan yang menarik adalah tingkat stres berkaitan dengan seberapa jauh mereka menonton televisi mengenai bencana tersebut. Pada survei yang lebih belakangan pada penduduk Manhattan yang dilakukan 5 hingga 8 minggu setelah jatuhnya World Trade Center dipublikasikan di New England Journal of MedicineI pada tahun 2002, survei ini menemukan bahwa 9,8 persen—atau sekitar 90.000 orang—memiliki PTSD atau depresi klinis. Sebanyak 3,7 persen lainnya—atau perkisaan 340.000 orang—memenuhi kriteria diagnostik kedua diagnosis tersebut. Angka yang lebih tinggi untuk kedua gangguan ditemukan pada orang yang tinggal dekat dengan tempat kejadian, menderita peristiwa penuh tekanan lainnya selama 12 bulan sebelumnya, atau memiliki pengalaman panik hebat selama atau segera setelah serangan. Angka kedua gangguan lebih tinggi pada responden Hispanik dibandingkan responden kulit putih, hitam, atau Asia, dan lebih tinggi pada perempuan dibandingkan laki-laki. Di antara orang-orang dengan tingkat penghasilan lebih tinggi, insiden ini lebih rendah untuk gangguan tersebut. Akhirnya, satu studi yang dilakukan pada lebih dari 8.000 anak berusia 10 hingga 13 tahun yang tinggal di New York saat serangan teroris menemukan bahwa 11 persen dari mereka memiliki gejala yang sesuai dengan diagnosis PTSD 9 bulan setelah peristiwa. Limabelas persen lainnya memiliki gejala agorafobia (cth., takut naik alat transportasi umum). serupa dengan demografi pada dewasa yang dijelaskan di atas, siswa Hispanik dan anak perempuan terkena dalam proporsi yang lebih besar, seperti mereka yang terpajan peristiwa traumatik yang tidak berkaitan sebelumnya. DIAGNOSIS BANDING Pertimbangan utama dalam diagnosis PTSD adalah kemungkinan bahwa pasien juga menderita cedera kepala selama trauma. Pertimbangan organik lain yang dapat menyebabkan dan memperberat gejala adalah epilepsi, gangguan penggunaan alkohol, dan gangguan terkait zat lain. Intoksikasi akut atau putus zat juga dapat menunjukkan gambaran klinis yang sulit dibedakan dengan gangguan ini sampai efek zat hilang. PTSD lazim salah didiagnosis sebagai gangguan jiwa lain dan kemudian diobati dengan tidak sesuai. Klinisi harus mempertimbangkan diagnosis PTSD pada pasien yang memiliki gangguan nyeri, penyalahgunaan zat, gangguan ansietas lain, dan gangguan mood. Pada umumnya, PTSD dapat dibedakan dengan gangguan jiwa lain dengan mewawancarai pasien mengenai pengalaman traumatik sebelumnya dan dengan sifat gejala saat ini. Gangguan kepribadian ambang, gangguan disosiatif, gangguan buatan, dan malingering, juga harus dipertimbangkan. Gangguan kepribadian ambang dapat sulit dibedakan dengan PTSD. Kedua gangguan ini dapat ada bersamaan atau bahkan penyebabnya dapat berkaitan. Pasien dengan gangguan disosiatif biasanya tidak memiliki derajat perilaku menghindar, hyperarousal autonom, atau riwayat trauma yang dimiliki pasien PTSD. Sebagian karena publisitas yang didapat PTSD, klinisi juga harus mempertimbangkan kemungkinan gangguan buatan dan malingering. PERJALANAN GANGGUAN DAN PROGNOSIS PTSD biasanya timbul beberapa waktu setelah trauma. Penundaan dapat selama 1 minggu atau hingga 30 tahun. Gejala dapat berfluktuasi dari waktu ke waktu dan menjadi paling intens selama periode stres. Jika tidak diobati, sekitar 30 persen pasien akan pulih sempurna, 40 persen akan terus memiliki gejala ringan, 20 persen akan terus memiliki gejala sedang, dan 10 persen tetap tidak berubah atau bertambah buruk. Setelah satu tahun, sekitar 50 persen akan pulih. Prognosis yang baik diperkirakan dengan adanya awitan gejala cepat, durasi gejala singkat (kurang dari 6 bulan), fungsi pramorbid baik, dukungan sosial baik, dan tidak adanya gangguan psikiatri, medis, atau gangguan terkait zat lain atau faktor risiko lain.\ Umumnya, orang yang sangat muda dan sangat tua lebih memiliki kesulitan dengan peristiwa traumatik daripada orang usia pertengahan. Contohnya, sekitar 80 persen anak yang masih kecil yang mengalami cedera terbakar menunjukkan gejala PTSD 1 atau 2 tahun setelah cedera awal; hanya 30 persen orang dewasa yang menderita cedera yang sama mengalami PTSD setelah 1 tahun. Kemungkinan, anak yang masih kecil belum memiliki mekanisme koping ynag adekuat untuk menghadapi akibat buruk emosional dan fisik trauma. Sama halnya dengan orang yang sudah tua, yang bila dibandingkan dengan orang dewasa yang lebih muda, cenderung memiliki mekanisme koping yang lebih kaku dan kurang dapat menggunakan pendekatan fleksibel dalam menghadapi efek trauma. Lebih jauh lagi, efek traumatik dapat diperberat ketidakmampuan sistem saraf dan sistem kardiovaskular, seperti berkurangnya aliran darah otak, gangguan penglihatan, palpitasi dan aritmia. Ketidakmampuan psikiatri yang sebelumnya ada, baik gangguan kepribadian atau suatu keadaan yang lebih serius, juga meningkatkan efek stresor tertentu. PTSD yang terjadi bersamaan dengan gangguan lain sering lebih berat, dapat lebih kronis, dan dapat sulit diobati. Ketersediaan dukungan sosial juga dapat memengaruhi timbulnya, keparahan, dan durasi PTSD. Umumnya, pasien yang memiliki jaringan dukungan sosial yang baik lebih kecil kemungkinannya memiliki gangguan ini dan lebih jarang mengalami PTSD dalam bentuk yang berat, serta lebih besar kemungkinannya pulih dalam waktu yang lebih singkat. TERAPI Ketika klinisi menghadapi pasien yang telah mengalami trauma bermakna, pendekatan utamanya adalah dukungan, dorongan untuk mendiskusikan peristiwa tersebut, dan edukasi mengenai berbagai mekanisme koping (contohnya relaksasi). Penggunaan sedatif dan hipnotik juga dapat membantu. Ketika pasien mengalami peristiwa traumatik di masa lalu dan sekarang memiliki PTSD, penekanan harus pada edukasi mengenai gangguan dan terapinya, baik farmakologis maupun psikoterapeutik. Klinisi juga harus bekerja untuk menghilangkan stigma pada penyakit jiwa dan PTSD. Farmakoterapi Selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI), seperti sertralin (Zoloft) dan paroksetin (Paxil) dipertimbangkan sebagai terapi lini pertama untuk PTSD karena efektivitas, tolerabilitas, dan tingkat keamanannya. SSRI mengurangi gejala semua kelompok gejala PTSD dan efektif dalam memperbaiki gejala PTSD yang khas, tidak hanya gejala yang serupa dengan depresi atau gangguan ansietas lain. Efektivitas imipramin (Tofranil) dan amitriptilin (Elavil), dua obat trisiklik, untuk terapi PTSD didukung oleh sejumlah percobaan klinis yang terkontrol baik. walalupun beberapa percobaan kedua obat tersebut memberikan temuan negatif, sebagian besar percobaan ini memiliki kecacatan desain yang serius, termasuk durasi yang terlalu isngkat. Dosis imipramin dan amitriptilin harus sama dengan dosis yang digunakan untuk mengobati gangguan depresif, dan lama minimum suatu percobaan yang adekuat adalah 8 minggu. Pasien yang memberikan respons baik mungkin harus meneruskan farmakoterapi sedikitnya satu tahun sebelum dicoba penghentian obat. Sejumlah studi menunjukkan bahwa farmakoterapi lebih efektif dalam tatalaksana depresi, ansietas, dan hyperarousal, daripada tatalaksana penghindaran, penyangkalan, dan penumpulan emosional. Obat lain yang dapat berguna dalam terapi PTSD adalah monoamine oxidase inhibitors (MAOI) (cth., fenelzin [Nardil], trazodon [Desyrel], dan antikonvulsan (contohnya karbamazepin (Tegretol) dan valproat [Depakenel]). Sejumlah studi juga mengungkapkan perbaikan PTSD pada pasien yang diberikan reversible monoamine oxidase inhibitors (RIMA) seperti brofaromin. Penggunaan klonin (Catapres) dan propranolol (Inderal), yang merupakan agen antiadrenergik pada gangguan ini. Hampir tidak ada data positif mengenai penggunaan antipsikotik pada gangguan ini sehingga penggunaan obat ini—contohnya haloperidol (Haldol)—harus dicadangkan untuk kontrol jangka pendek agresi dan agitasi berat. Psikoterapi Psikoterapi psikodinamik dapat berguna dalam terapi pada banyak pasien PTSD. Di sejumlah kasus, rekonstruksi peristiwa traumatik dengan abreaksi dan katarsis terkait dapat bersifat terapeutik, tetapi psikoterapi harus diindividualisasi, karena mengalami kembali trauma dapat terlalu berat untuk sejumlah pasien. Intervensi psikoterapeutik PTSD mencakup terapi perilaku, terapi kognitif, dan hipnosis. Banyak klinisi menyarankan psikoterapi terbatas waktu untuk korban trauma. Terapi seperti ini biasanya memerlukan pendekatan kognitif dan juga memberikan dukungan serta keamanan. Sifat psikoterapi jangka pendek meminimalkan risiko ketergantungan dan menjadi kronis, tetapi masalah kecurigaan, paranoid, dan kepercayaan sering memberi pengaruh buruk terhadap kepatuhan. Terapis harus menghadapi penyangkalan pasien mengenai peristiwa traumatik, menyarankan mereka bersantai, dan menjauhkan mereka dari sumber stres. Pasien harus disarankan tidur, menggunakan obat jika perlu. Dukungan dari orang di lingkungan mereka (seperti teman dan kerabat) harus diberikan. Pasien harus diminta mengingat kembali dan melakukan abreaksi perasaan emosional yang berkaitan dengan peristiwa traumatik dan merencanakan pemulihan masa mendatang. Abreaksi— mengalami emosi yang berkaitan dengan suatu peristiwa—dapat membantu bagi sejumlah pasien. Wawancara dengan amobarbital (Amytal) telah digunakan untuk mempermudah proses ini. Psikoterapi setelah peristiwa traumatik harus mengikuti model intervensi krisis dengan dukungan edukasi, dan pembentukan mekanisme koping serta penerimaan peristiwa. Ketika timbul PTSD, dua pendekatan psikoterapeutik utama dapat diambil. Pendekatan pertama adalah pajanan terhadap peristiwa traumatik melalui teknik membayangkan atau pajanan in vivo. Pajanan ini dapat intens seperti pada terapi implosif, atau bertahap seperti pada desensitisasi sistematik. Pendekatan kedua adalah mengajari pasien metode penatalaksanaan stres, termasuk teknik relaksasi dan pendekatan kognitif untuk menghadapi stres. Sejumlah data pendahuluan menunjukkan bahwa walaupun teknik penatalaksanaan stres efektif lebih cepat daripada teknik pemakanan, hasil teknik pemajanan lebih bertahan lama. Teknik psikoterapeutik lainnya yang relatif baru dan kontroversial adala eye movement desesitization and reprocessing (EMDR), di sini pasien berfokus pada gerakan lateral jari klinisi sambil mempertahankan bayangan mental tentang pengalaman trauma. Keyakinan umum adalah bahwa gejala dapat dipulihkan jika pasien mengingat peristiwa traumatik sambil berada dalam keadaan relaksasi dalam. Penggagas terapi ini mengatakan terapi ini sama efektif dan mungkin lebih efektif daripada terapi PTSD laind an lebih disukai klinisi maupun pasien yang telah mencobanya. Di samping teknik terapi individual, terapi kelompok dan terapi keluarga sering dilaporkan efektif pada kasus PTSD. Keuntungan terapi kelompok mencakup saling berbagi pengalaman traumatik dan dukungan dari anggota kelompok lain. Terapi kelompok terutama berhasil pada veteran Vietnam dan orang yang selamat dari bencana menakutkan seperti gempa bumi. Terapi keluarga sering membantu mempertahankan perkawinan saat periode gejala memberat. Rawat inap dapat diperlukan jika gejala berat atau jika terdapat risiko bunuh diri maupun kekerasan lain.