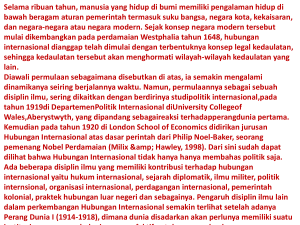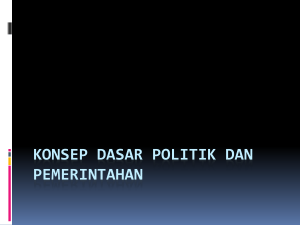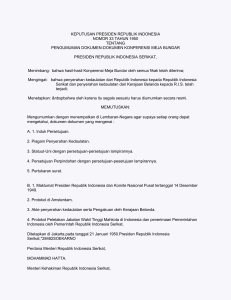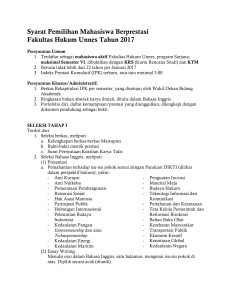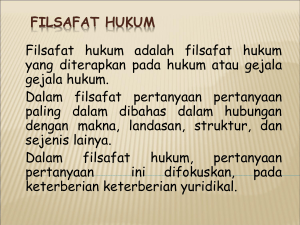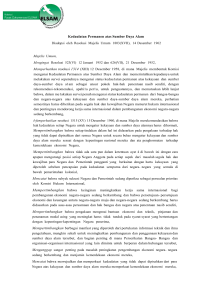RESPONSIBILITY TO PROTECT : SUATU TANGGUNG JAWAB
advertisement

RESPONSIBILITY TO PROTECT : SUATU TANGGUNG JAWAB DALAM KEDAULATAN NEGARA Santa Marelda Saragih ________________________________________________________________________ Abstract “The time of absolute sovereignty … has passed; its theory was never matched by reality.” − Boutros Boutros-Ghali Violations of human rights which occur in several countries engender a question pertaining to legality of humanitarian intervention. Doctrine of Humanitarian intervention conflicts with the fundamental principle of state sovereignty. The conflict between the principle of state sovereignty and humanitarian intervention has constructed a dilemma condition in conducting the enforcement of human rights. Humanitarian intervention aims to protect civilians from the violation of human rights, The foregoing notion is a challenge to the efforts of civilian protection as a part of the subjects of international law and international community. As the answer of this challenge, a new concept is required to bridge the principle of state sovereignty and the enforcement of human rights. That new concept is Responsibility to Protect which adhere in state sovereignty. In the 2005 World Summit, Member States included R to P in the Outcome Document agreeing to Paragraphs 138 and 139. These paragraphs gave final language to the scope of R to P and to whom the responsibility actually falls. In April 2006, the United Nations Security Council reaffirmed the provisions of paragraphs 138 and 139 in resolution (S/RES/1674), thereby formalizing their support for the norm. The next major advancement in R to P came in January 2009, when UN Secretary-General Ban Ki-moon released a report called Implementing the Responsibility to Protect. This report argued for the implementation of R to P and outlined the three principles of R to P. The norm of Responsibility to Protect has changed the paradigm of state sovereignty from an absolute authority to a primary responsibility for giving protection to civilians. Pendahuluan Negara sebagai subyek hukum internasional memiliki unsur istimewa yang tidak dimiliki oleh subyek-subyek hukum internasional lainnya dan unsur tersebut adalah kedaulatan.87 Kedaulatan merupakan dasar utama yang menjadi acuan prinsip non intervensi dalam praktek hukum internasional.88 Seiring dengan perkembangan hukum internasional, kedaulatan negara mengalami konflik dengan intervensi kemanusiaan yang menimbulkan suatu pertanyaan tentang legalitas keterlibatan negara−negara lain untuk melakukan intervensi kemanusiaan di wilayah territorial suatu negara. Dalam 87 Konvensi Montevideo 1933 Pasal 1 ayat 1. Dalam hukum internasional terdapat suatu prinsip umum yang dinamakan dengan "Par Imparem Non Hebet Imperium" yang berarti "Tidak ada suatu negara berdaulat manapun yang dapat menaklukkan negara berdaulat lainnya". Prinsip ini mendasari persamaan kedaulatan antar negara−negara dalam hukum internasional. 88 International Conference On New Conflicts And The Challenge Of The Protection Of The Civilian Population yang diadakan oleh International Institute of Humanitarian Law (IIHL) bekerjasama dengan Istituto Affari Internazionali (IAI) pada tanggal 14 Desember 2010, di Kementerian Luar Negeri Italia, masalah di atas menjadi salah satu topik yang didiskusikan dan para ahli hukum humaniter internasional menyatakan bahwa konflik antara kedaulatan dengan intervensi kemanusiaan merupakan tantangan baru bagi upaya perlindungan terhadap masyarakat sipil. Pada tahun 1994 terjadi suatu kasus genosida (genocide) di Rwanda yang memakan korban sebanyak 850.000 orang suku Tutsi. Pembunuhan massal (mass murder) terhadap suku Tutsi tersebut dikomando oleh Akazu yang merupakan kelompok mayoritas suku Hutu di Rwanda. Menanggapi kasus genosida di Rwanda dan kegagalan komunitas internasional untuk melakukan intervensi kemanusiaan, Sekjen PBB Kofi Annan memberikan suatu pertanyaan, "Kapankah komunitas internasional dapat melakukan intervensi untuk melindungi masyarakat sipil ?" Pertanyaan ini secara implisit memberikan wacana tentang tanggung jawab komunitas internasional untuk melindungi masyarakat sipil dari pelanggaran−pelanggaran hak asasi manusia serta mempertanyakan legalitas intervensi kemanusiaan yang selama ini bertentangan dengan kedaulatan negara. Selain kasus genosida di Rwanda terdapat beberapa kasus lain yang menjadi landasan bagi pertanyaan Kofi Annan di atas, kasus−kasus tersebut , yaitu Genosida terhadap suku Kurdi di Irak pada tahun 1987, konflik di Kosovo pada tahun 1998 sampai dengan 1999, dan konflik Darfur pada tahun 2003. Berkaitan dengan kasus Kosovo, Kofi Annan berpendapat bahwa prinsip kedaulatan negara di satu sisi menghalangi Dewan Keamanan untuk melakukan intervensi, namun di sisi lain terdapat kewajiban moral dari komunitas internasional untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Kedua pandangan tersebut menimbulkan suatu kondisi yang dilematis dalam penegakan hak asasi manusia. Meresponi kondisi ini, Kofi Annan menyatakan bahwa perlu adanya prinsip−prinsip universal yang dapat menjadi dasar atas legitimasi intervensi kemanusiaan untuk mendukung penegakan hak asasi manusia.89 Intervensi kemanusiaan mengandung makna "campur tangan" atau keterlibatan negara lain terhadap permasalahan kemanusiaan yang terjadi di wilayah kedaulatan negara tertentu dan hal ini bertentangan dengan kedaulatan negara yang bersangkutan. Untuk menghubungkan kewajiban untuk melindungi masyarakat sipil dari pelanggaran hak asasi manusia di satu sisi dengan kedaulatan negara di sisi lain dibutuhkan suatu konsep tindakan kemanusiaan (humanitarian action) dalam format yang baru. Format baru dari tindakan kemanusiaan yang sedang menjadi pembahasan negara−negara anggota Perserikatan Bangsa−Bangsa saat ini adalah "Responsibility to Protect" atau tanggung jawab untuk melindungi. Prinsip Responsibility to Protect (RtoP) tercantum dalam paragrapf 138 dan 139 dari the 2005 World Summit Outcome Document. Prinsip ini kemudian ditegaskan kembali oleh Dewan Keamanan PBB (United 89 Pernyataan asli Kofi Annan : "Just as we have learned that the world cannot stand aside when gross and systematic violations of human rights are taking place, so we have also learned that intervention must be based on legitimate and universal principles if it is to enjoy the sustained support of the world's peoples. This developing international norm in favour of intervention to protect civilians from wholesale slaughter will no doubt continue to pose profound challenges to the international community." Dikutip dari Humanitarian Action And State Sovereignty, International Institute of Humanitarian Law , 2001, hal.38. Nations Security Council) dalam Resolusi S/RES/1674 dan diuraikan kembali pada bulan Januari 2009 oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa−Bangsa, Ban Ki−moon, dalam laporannya yang dinamakan dengan Implementing the Responsibility to Protect. Legitimasi Kedaulatan Negara Dalam Hukum Internasional Dalam hukum internasional, kedaulatan negara merupakan prinsip yang mendasari hubungan antar negara dan juga merupakan landasan dari tatanan dunia. Prinsip ini merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional (international customary law) yang tercantum dalam Piagam PBB (United Nations Charter) serta menjadi komponen penting dalam upaya pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia. Kedaulatan negara menunjukkan kompetensi, independensi dan kesetaraan hukum antar negara−negara. Dengan demikian setiap negara yang berdaulat memiliki kebebasan untuk bertindak dalam lapangan hukum internasional tanpa gangguan atau campur tangan dari negara−negara berdaulat lainnya. Kebebasan bertindak ini mencakup pilihan sistem politik, ekonomi, sosial, budaya dan pembentukan kebijakan luar negeri. Ruang lingkup dari kebebasan di atas bersifat tidak terbatas, tergantung pada perkembangan hukum internasional dan hubungan internasional. Dasar hukum internasional yang menjadi landasan prinsip kedaulatan negara adalah perjanjian Westhpalia 1648 yang dibentuk oleh negara−negara Eropa.90 Perjanjian Westphalia 1648 meletakkan dasar−dasar masyarakat internasional modern dimana setiap negara memiliki kedaulatan penuh yang dilandasi oleh kemerdekaan dan persamaan derajat dalam praktek hukum internasional dan hubungan internasional. Unsur−unsur negara yang berdaulat dikodifikasikan dalam Konvensi Montevideo 1933 Tentang Hak−hak dan Kewajiban Negara ( Montevideo Convention on the Rights and Duties of States ). Unsur−unsur tersebut terdiri dari populasi yang permanen ( permanent population ), wilayah territorial ( defined territory ) dan pemerintah yang berdaulat (sovereign government). Komponen terpenting dari kedaulatan terwujud dalam kekuasaan negara−negara untuk bertindak di wilayah territorial negara−negara tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Piagam PBB, organisasi dunia didasarkan atas prinsip persamaan kedaulatan dari semua negara−negara anggota. Disamping menjadi dasar dalam hubungan internasional, prinsip persamaan kedaulatan ini juga menjadi dasar pembentukan organisasi antar pemerintah yang diberikan kapasitas untuk bertindak dalam hubungan antar negara−negara sesuai dengan kerangka kerja yang ditetapkan oleh organisasi tersebut. Pada tahun 1949, Mahkamah Internasional (International Court of Justice) mengamati bahwa diantara negara−negara merdeka, penghormatan terhadap wilayah kedaulatan merupakan suatu pondasi utama dari hubungan internasional. Tiga puluh tahun kemudian, Mahkamah Internasional menjadikan prinsip kedaulatan negara sebagai prinsip fundamental dalam menyelesaikan sengketa antar negara. Prinsip non intervensi dalam lingkup yurisdiksi nasional negara−negara merupakan jangkar bagi kedaulatan negara dalam sistem hubungan internasional dan kewajiban−kewajiban internasional. Yurisdiksi merupakan kekuasaan, otoritas dan kompetensi dari suatu negara untuk memerintah warga negara dan seluruh kekayaan negara yang berada di wilayah negara yang bersangkutan. Yurisdiksi terdiri dari dua 90 Stephen John Stedman, “Alchemy for a New World Order: Overselling ‘Preventive Diplomacy’,” Foreign Affairs 74, no. 3 (May–June 1995), pp. 14–20. kategori yang dinamakan dengan prescriptive jurisdiction dan enforcement jurisdiction. Prescriptive jurisdiction berkaitan dengan kekuasaan dari suatu negara untuk memberlakukan hukum baik di dalam maupun di luar wilayah teritorialnya dan enforcement jurisdiction adalah kekuasaan negara untuk melakukan penegakan hukum di dalam wilayah teritorialnya. Yurisdiksi berasal dari kedaulatan negara atas wilayah teritorialnya, namun dapat diperluas diluar batas teritorial tersebut.91 Perserikatan Bangsa−Bangsa secara eksplisit menyatakan larangan untuk melakukan tindakan intervensi terhadap urusan domestik negara−negara anggotanya. Ketentuan mengenai hal tersebut tercantum dalam Article 2 (7) UN Charter yang mengatur bahwa tidak ada satupun ketentuan dalam Piagam PBB (UN Charter) yang memberikan kuasa kepada PBB untuk melakukan intervensi dalam masalah−masalah yang berkaitan dengan yurisdiksi nasional negara−negara anggotanya atau mengharuskan negara−negara anggota untuk mengajukan permohonan apabila hendak menyelesaikan masalah−masalah yang sedang mereka hadapi dengan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam UN Charter.92 Ada beberapa batas –batas penting dari kedaulatan negara dan yurisdiksi nasional yang diterima secara meluas dalam hukum internasional. Batasan pertama adalah ketegangan yang terjadi antara kedaulatan, kemerdekaan dan persamaan kedudukan diantara negara−negara di satu sisi dan kewajiban internasional yang bersifat kolektif untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional di sisi lain. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Bab VII UN Charter, kedaulatan bukanlah suatu penghalang bagi Dewan Keamanan untuk melakukan upaya−upaya untuk menyikapi suatu ancaman terhadap perdamaian, suatu pelanggaran terhadap perdamaian atau suatu tindakan agresi.93 Dengan kata lain, kedaulatan negara−negara sebagaimana yang diatur dalam UN Charter akan mendukung upaya−upaya perwujudan keamanan dan perdamaian internasional. Status dari persamaan kedaulatan negara akan berjalan dengan efektif ketika negara−negara berada dalam tatanan internasional yang stabil dan damai. Batasan ke dua berkaitan dengan kedaulatan negara yang dibatasi oleh kebiasaan dan kewajiban perjanjian (treaty obligation) baik dalam hubungan internasional maupun hukum internasional. Negara−negara bertanggung jawab secara hukum atas pelaksanaan kewajiban internasional mereka dan kedaulatan negara tidak dapat dijadikan alasan dari kelalaian mereka dalam pemenuhan kewajiban internasional tersebut. Kewajiban yang dipikul oleh negara sebagai konsekuensi keanggotaan mereka di PBB mensyaratkan suatu pembatasan dari kedaulatan negara−negara anggota sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam UN Charter. Secara khusus Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa untuk menjamin seluruh hak dan manfaat dari keanggotaan, negara−negara anggota harus 91 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Yurisdiksi merupakan prima facie yang bersifat eksklusif atas wilayah territorial suatu negara beserta populasi yang ada di wilayah negara tersebut dan kewajiban non intervensi dalam urusan dalam negeri yang melindungi baik kedaulatan territorial maupun yurisdiksi nasional negara−negara dalam suatu basis yang sama. 92 Article 2 (7) UN Charter : “[n]othing contained in the present Charter shall authorise the United Nations to intervene in matters that are essentially within the domestic jurisdiction of any State or shall require the Members to submit suchmatters to settlement under the present Charter.” 93 Christopher M. Ryan, “Sovereignty, Intervention, and the Law: A Tenuous Relationship of Competing Principles,” Millennium: Journal of International Studies 26 (1997), p. 77; and Samuel M. Makinda,“Sovereignty and International Security: Challenges for the United Nations,” Global Governance 2, no. 2(May–August 1996), hal. 149. memenuhi kewajiban−kewajiban yang mereka pikul dengan niat baik sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UN Charter. Lebih lanjut lagi, sesuai dengan tujuan dan prinsip−prinsip yang berlaku, pasal di atas juga mewajibkan negara−negara anggota untuk mewujudkan kerja sama internasional dalam mengatasi masalah−masalah ekonomi, sosial, budaya, mempromosikan serta mendukung penghormatan terhadap hak−hak asasi manusia dan untuk kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa dan agama. Pasal ini lebih lanjut mengakui PBB sebagai pusat harmonisasi dari tindakan−tindakan negara pada akhir pencapaian tujuan. Dengan demikian UN Charter mengangkat solusi ekonomi, sosial, budaya, kemanusiaan serta hak asasi manusia untuk lingkup internasional. Sesuai dengan lingkup internasional, masalah−masalah di atas tidak dapat dianggap sebagai masalah yang bersifat domestik dan solusi tidak dapat hanya diterapkan secara eksklusif dalam kedaulatan negara. Kedaulatan yang dimiliki oleh negara−negara pada hakikatnya memuat tanggung jawab dasar untuk melindungi individu−individu, harta benda dan untuk menjalankan fungsi pemerintahan di wilayah terirorial masing−masing negara tersebut. Cakupan dari tanggung jawab dari pemerintahan telah membawa perubahan yang signifikan terhadap kedaulatan negara sejak tahun 1945. Khususnya, sejak penandatanganan UN Charter, terdapat suatu jaringan yang meluas dari kewajiban−kewajiban di bidang hak asasi manusia. Hal ini membentuk serangkaian kewajiban−kewajiban negara untuk melindungi individu dan harta bendanya serta untuk mengatur hubungan politik dan ekonomi. Perkembangan ini memberikan suatu paradigm baru dalam hukum internasional bahwa kedaulatan negara tidak dapat dijadikan dasar atau alasan untuk melindungi pelanggaran hak asasi manusia dalam lingkup internal yang bertentangan dengan kewajiban−kewajiban internasional. Seiring dengan perkembangan hukum internasional dan hubungan internasional, kedaulatan telah terkikis oleh faktor−faktor ekonomi, lingkungan dan budaya. Intervensi yang sebelumnya dianggap sebagai hubungan internal oleh negara−negara lain, sektor swasta dan aktor bukan negara (non state actor) telah menjadi suatu rutinitas. Namun , yang menjadi masalah bukanlah rutinitas tersebut melainkan suatu potensi ketegangan ketika prinsip kedaulatan negara dan penderitaan umat manusia berada dalam posisi yang berdampingan.94 Perdebatan Mengenai Intervensi Kemanusiaan Keberadaan kedaulatan negara sebagai prinsip yang bersifat fundamental dalam hukum internasional melahirkan prinsip lain yang dinamakan prinsip non− intervensi. Prinsip non−intervensi merupakan kewajiban setiap negara berdaulat untuk tidak melakukan tindakan mencampuri urusan dalam negeri dari negara lain dalam relasi antar negara.95 Dalam hukum internasional, doktrin intervensi kemanusiaan (humanitarian intervention) telah menimbulkan suatu perdebatan . Perdebatan ini timbul karena doktrin 94 Seperti yang dikatakan oleh Kofi Annan dalam kata sambutannya pada General Assembly Tahun 1999: “States bent on criminal behaviour[should] know that frontiers are not the absolute defence.” In this respect, events in thelast decade have broken new ground." 95 Dalam kasus Corfu Channel ( United Kingdom v. Albania :1946), International Court of Justice meneguhkan prinsip non−intervensi dengan mengatakan: "Between independent states, respect for territorial sovereignty is an essential foundation of international relations." tersebut berhadapan langsung dengan prinsip kedaulatan negara dan prinsip non−intervensi. Ketentuan Pasal 2 (1), Pasal 2 (4), Pasal 2 (7) Piagam PBB dengan jelas menyatakan bahwa dalam hubungan antar negara tidak diperbolehkan adanya intervensi. Pengaturan tentang hal ini semakin dipertegas dengan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2625 (XXV) yang dikeluarkan pada tanggal 24 Oktober 1970. Resolusi ini kemudian diterima sebagai Deklarasi Majelis Umum Tentang Prinsip−Prinsip Hukum Internasional Mengenai Hubungan Persahabatan dan Kerja Sama Antar Negara yang berkaitan dengan Piagam PBB (Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations). Dengan demikian terjadi suatu pertentangan atau konflik antara kedaulatan negara dengan intervensi kemanusiaan. Para pendukung konsep intervensi kemanusiaan berargumen bahwa Intervensi kemanusiaan memperoleh legitimasinya berdasarkan penafsiran atas Pasal 2 (4) Piagam PBB yang menyatakan: "All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations." Ketentuan pasal di atas bukanlah sebuah larangan absolut melainkan suatu batasan agar suatu intervensi tidak melanggar kesatuan wilayah (territorial integrity), kebebasan politik (political independence) dan tidak bertentangan dengan tujuan PBB (in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations). Menurut hasil penelitian D'Amato, kesatuan wilayah dimaksudkan jika sebuah negara kehilangan wilayahnya secara permanen sedangkan dalam intervensi kemanusiaan, pihak yang melakukan intervensi tidak mengambil wilayah negara secara permanen, tindakan tersebut hanya untuk melakukan penegakan hak asasi manusia. Intervensi kemanusiaan dapat dikatakan sah secara hukum internasional apabila tidak melanggar batasan yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 2(4) Piagam PBB di atas. Legalitas intervensi kemanusiaan kemudian juga dihubungkan dengan tujuan PBB untuk menghormati hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1(3) Piagam PBB yang menyatakan: To achieve international co-operation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion. Sejak lahirnya Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948 dan Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide pada tahun 1949, kedaulatan negara menjadi suatu entitas yang memuat kewajiban internasional dalam bidang penegakan hak asasi manusia. Hans Kelsen menyatakan bahwa tujuan adanya hukum internasional adalah untuk membatasi kedaulatan negara itu sendiri. Sejak individu menjadi subyek hukum internasional, maka pada hakikatnya kedaulatan negara itu diperoleh dari individu−individu yang mendelegasikan kewenangannya kepada negara. Jadi, ketika negara telah melanggar hak−hak individu, maka individu tersebut dapat meminta bantuan kepada pihak lain untuk memulihkan hak−hak mereka. Dalam kondisi ini, intervensi kemanusiaan terjadi dan timbul kewajiban negara untuk melakukan kerja sama antar negara−negara untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia. Praktek– praktek yang dilakukan oleh negara−negara saat ini juga telah menimbulkan sebuah preseden, bahwa intervensi kemanusiaan dapat dianggap sebagai kebiasaan internasional. Doktrin intervensi kemanusiaan lahir ketika terjadi suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Intervensi tersebut dapat dilakukan baik secara individual maupun kolektif. Koalisi pasukan militer Amerika Serikat, Inggris dan Perancis yang dikirimkan ke Irak pada tahun 1991 merupakan salah satu praktek negara dalam intervensi kemanusiaan. Koalisi ini dibentuk sebagai respon terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB No 688 yang mengutuk tindakan pemerintah Irak kepada suku Kurdi.96 Dalam resolusi tersebut, Dewan Keamanan tidak menyebutkan baik suatu tindakan bersenjata kolektif maupun intervensi dengan menggunakan senjata. Namun, beberapa bulan kemudian, ketiga negara di atas melakukan " Operation Provide Comfort "97 di Irak Utara dengan alasan kemanusiaan. Javier Perez de Cuellar, Sekretaris Jenderal PBB pada saat itu menyebutkan bahwa operasi tersebut dapat melanggar kedaulatan Irak apabila tidak ada izin dari pemerintah Irak atau otorisasi dari Dewan Keamanan PBB. Namun, di sisi lain Javier juga mengungkapkan pentingnya tindakan atas dasar tujuan moral dan kemanusiaan. Untuk melegalisasi tindakan koalisi tersebut, akhirya Irak memberikan izinnya kepada PBB untuk mengirim bantuan kemanusiaan ke Irak Utara. Pengaturan mengenai intervensi kemanusiaan tidak diatur secara eksplisit dalam Piagam PBB. Disamping itu juga tidak terdapat Putusan Mahkamah Internasional (International Court of Justice) yang melegitimasi suatu intervensi kemanusiaan. Putusan Mahkamah Internasional dalam kasus Nikaragua melawan Amerika, membatalkan alasan Amerika yang mendasari bahwa kekuatan bersenjata yang dilakukan oleh negara tersebut merupakan suatu tindakan legal atas dasar perlindungan terhadap hak asasi manusia. Mahkamah Internasional menolak alasan pembelaan Amerika Serikat karena tindakan bersenjata yang dilakukan dengan alasan kemanusiaan oleh negara tersebut tidak relevan dengan kenyataan yang terjadi. Amerika Serikat telah melakukan peledakan dermaga dan instalasi minyak yang tidak memiliki korelasi dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Namun, Mahkamah Internasional tidak menyatakan secara eksplisit bahwa intervensi kemanusiaan bertentangan dengan hukum internasional. Dari uraian−uraian di atas dapat dikatakan bahwa kedaulatan negara yang bersifat fundamental dalam hukum internasional masih mengalami benturan atau pertentangan dengan intervensi kemanusiaan. Responsibility to Protect Sebagai Tanggung Jawab Dalam Kedaulatan Negara Konflik atau pertentangan antara prinsip kedaulatan negara dengan intervensi kemanusiaan telah menciptakan suatu kondisi yang dilematis dalam penegakan hak asasi manusia. Seperti yang telah dikemukakan dalam pokok bahasan sebelumnya, intervensi kemanusiaan mengandung makna suatu tindakan negara lain yang melibatkan diri dalam masalah kemanusiaan atau pelanggaran hak asasi manusia dalam lingkup domestik yang terjadi di wilayah kedaulatan negara lain. Tindakan intervensi ini di satu sisi memiliki tujuan moral untuk melindungi masyarakat sipil, namun di sisi lain melanggar prinsip kedaulatan yang sangat fundamental dalam hukum internasional. Hal di atas merupakan tantangan bagi upaya perlindungan warga sipil yang merupakan bagian dari subyek hukum internasional maupun komunitas internasional. Sebagai jawaban dari tantangan ini perlu adanya suatu konsep baru yang dapat menjadi penghubung antara prinsip 96 RESOLUTION 688 (1991) Adopted by the Security Council at its 2982nd meeting on 5 April 1991, http://www.fas.org/news/un/iraq/sres/sres0688.htm. 97 Operation Provide Comfort, http://www.globalsecurity.org/military/ops/provide. kedaulatan negara dan penegakan hak asasi manusia dalam lingkup internasional. Konsep baru tersebut adalah konsep Responsibility to Protect atau tanggung jawab untuk melindungi yang terkandung dalam kedaulatan negara. Dalam World Summit 2005, konsep Responsibility to Protect dimasukkan dalam dokumen yang merupakan hasil dari pertemuan ini. Konsep Responsibility to Protect (R to P) tercantum dalam paragraf 138 dan paragraf 139 yang menyatakan sebagai berikut: 138. Each individual State has the responsibility to protect its populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. This responsibility entails the prevention of such crimes, including their incitement, through appropriate and necessary means. We accept that responsibility and will act in accordance with it. The international community should, as appropriate, encourage and help States to exercise this responsibility and support the United Nations in establishing an early warning capability. 139. The international community, through the United Nations, also has the responsibility to use appropriate diplomatic, humanitarian and other peaceful means, in accordance with Chapters VI and VIII of the Charter, to help protect populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. In this context, we are prepared to take collective action, in a timely and decisive manner, through the Security Council, in accordance with the Charter, including Chapter VII, on a case−by−case basis and in cooperation with relevant regional organizations as appropriate, should peaceful means be inadequate and national authorities manifestly fail to protect their population from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity and its implications, bearing in mind the principles of the principles of the Charter and international law. We also intend to commit ourselves, as necessary and appropriate, to helping States build capacity to protect their populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity and to assisting those which are under stress before crises and conflict break out. Pada bulan April 2006, Dewan Keamanan PBB menegaskan kembali ketentuan−ketentuan dalam paragraph 138 dan 139 di atas dalam Resolusi S/Res/1674 sebagai bentuk dukungan formal terhadap norma Responsibility to Protect di atas. Perkembangan norma Responsibility to Protect selanjutnya terjadi pada bulan Januari 2009, ketika Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki−moon mengeluarkan suatu laporan yang disebut Implementing the Responsibility to Protect. Laporan ini berisi tentang perdebatan mengenai implementasi R to P dan mencantumkan tiga prinsip dari R to P. Prinsip – Prinsip tersebut adalah sebagai berikut : 1. Prinsip pertama menekankan bahwa negara−negara memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi warga negaranya dari genosida (genocide), kejahatan perang, penghapusan etnis (ethnic cleansing) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (mass atrocities); 2. Prinsip kedua menyatakan komitmen komunitas internasional untuk memberikan bantuan kepada negara−negara dalam peningkatan kapasitas untuk melindungi warga negara atau populasinya dari kejahatan terhadap kemanusiaan (mass atrocities ) dan membantu upaya perlindungan tersebut, yang difokuskan pada masa sebelum krisis terjadi dan pada saat konflik terjadi; 3. Prinsip ketiga memfokuskan pada tanggung jawab komunitas internasional untuk mengambil tindakan yang tepat pada waktunya untuk mencegah dan menghentikan kejahatan terhadap kemanusiaan (mass atrocities ), ketika suatu negara gagal untuk melindungi populasinya. Secara garis besar, Responsibility to Protect mencakup tiga tanggung jawab yang terdiri dari : 1. Tanggung jawab untuk mencegah (responsibility to prevent), merupakan tanggung jawab untuk menyikapi akar penyebab dan penyebab−penyebab langsung dari konflik internal serta krisis yang disebabkan oleh perbuatan manusia, yang mengakibatkan resiko terhadap populasi. 2. Tanggung jawab untuk bereaksi ( responsibility to react), merupakan tanggung jawab untuk meresponi situasi−situasi yang memaksa dilakukannya langkah−langkah yang tepat demi kepentingan kemanusiaan, yang dapat berupa upaya paksa seperti sanksi−sanksi dan penuntutan internasional, dan dalam kasus yang ekstrim dapat berupa intervensi militer. 3. Tanggung jawab untuk pemulihan ( responsibility to rebuild), tanggung jawab pemulihan (responsibility to rebuild) merupakan tanggung jawab untuk memberikan bantuan dalam proses rekonstruksi dan rekonsiliasi yang dilakukan setelah intervensi militer. Responsibility to React Responsibility to Protect Responsibility to Prevent Responsibility to Rebuild Konsep R to P yang telah dirumuskan dalam dokumen 2005 World Summit, Resolusi Dewan Keamanan PBB 1674 dan Laporan Sekretaris Jenderal PBB (Implementing the Responsibility to Protect) merupakan konsep yang lahir dari prinsip dasar−prinsip yang menyatakan bahwa:98 1. Kedaulatan negara mengandung suatu tanggung jawab pokok untuk melindungi warga negaranya yang berada dalam wilayah kedaulatan negara tersebut; 98 International Commision On Intervention and State Sovereignty, The Responsibility to Protect, www.iciss.ca/report-en.asp. 2. Ketika suatu populasi berada dalam keadaan bahaya akibat dari perang internal (internal war), pemberontakan (insurgency), penindasan atau kegagalan negara, dan negara tersebut berada dalam suatu kondisi tidak "berkehendak " (unwilling) atau "tidak berdaya" (unable) untuk menghentikan atau mencegahnya, prinsip non intervensi membenarkan tanggung jawab intenasional untuk melindungi (international responsibility to protect). Hal−hal yang menjadi pondasi dari R to P, sebagai pedoman bagi komunitas internasional yang terdiri dari negara−negara berdaulat antara lain: 1. Kewajiban−kewajiban yang melekat dalam konsep kedaulatan; 2. Tanggung jawab dari Dewan Keamanan PBB yang tercantum dalam Pasal 24 dari Piagam PBB untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional; 3. Kewajiban−kewajiban hukum khusus yang tercantum dalam deklarasi−deklarasi hak asasi manusia, kovenan, perjanjian internasional, hukum humaniter internasional dan hukum nasional; 4. Praktek yang berkembang yang dilakukan oleh negara−negara, organisasi regional dan Dewan Kewamanan PBB. Pemaparan tentang konsep Responsibility to Protect di atas telah memberikan jawaban terhadap suatu tantangan baru dalam hukum internasional. Paradigma kedaulatan negara telah mengalami perubahan dari suatu unsur yang bersifat absolut dan tidak dapat digugat menjadi suatu tanggung jawab mutlak untuk melindungi warga negaranya. Negara dan warga negara memiliki hubungan hukum yang bersifat timbal balik dalam wujud "kewarganegaraan". Kewarganegaraan menimbulkan suatu kewajiban dan hak yang seimbang antar negara dengan warga negaranya. Rasio hukum ini semakin memperkuat dasar untuk mengimplementasikan konsep Responsibility to Protect. Kegagalan komunitas internasional untuk melakukan intervensi kemanusiaan dalam kasus Genosida di Rwanda (1994), Bosnia (1994) dan Kosovo (1999) akibat pertentangan antara prinsip kedaulatan negara dengan intervensi kemanusiaan telah terjawab oleh suatu konsep baru yang dinamakan dengan Responsibility to Protect, suatu tanggung jawab dalam kedaulatan negara. Simpulan 1. Konflik atau pertentangan antara prinsip kedaulatan negara dengan intervensi kemanusiaan telah menciptakan suatu kondisi yang dilematis dalam penegakan hak asasi manusia. Konflik ini merupakan tantangan baru bagi upaya perlindungan terhadap masyarakat sipil dan diperlukan suatu konsep baru yang dapat menghubungkan kedaulatan negara dengan intervensi kemanusiaan. 2. Konsep baru tersebut adalah konsep Responsibility to Protect (R to P) atau tanggung jawab untuk melindungi yang melekat pada kedaulatan negara. Konsep R to P yang telah dirumuskan dalam dokumen 2005 World Summit, Resolusi Dewan Keamanan PBB 1674 dan Laporan Sekretaris Jenderal PBB (Implementing the Responsibility to Protect) merupakan konsep yang lahir dari prinsip dasar−prinsip yang menyatakan bahwa kedaulatan negara mengandung suatu tanggung jawab pokok untuk melindungi warga negaranya yang berada dalam wilayah kedaulatan negara tersebut.Ketika suatu populasi berada dalam keadaan bahaya akibat dari perang internal (internal war), pemberontakan (insurgency), penindasan atau kegagalan negara, dan negara tersebut berada dalam suatu kondisi tidak "berkehendak " (unwilling) atau "tidak berdaya" (unable) untuk menghentikan atau mencegahnya, prinsip non intervensi membenarkan tanggung jawab intenasional untuk melindungi (international responsibility to protect). R to P secara garis besar terdiri dari responsibility to prevent, responsibility to react dan responsibility to rebuild. 3. Paradigma kedaulatan negara telah mengalami pergeseran dari suatu unsur yang bersifat absolut dan tidak dapat digugat menjadi suatu tanggung jawab mutlak untuk melindungi warga negaranya. Negara dan warga negara memiliki hubungan hukum yang bersifat timbal balik dalam wujud "kewarganegaraan". Kewarganegaraan menimbulkan suatu kewajiban dan hak yang seimbang antar negara dengan warga negaranya. Rasio hukum ini semakin memperkuat dasar untuk mengimplementasikan konsep Responsibility to Protect. Rekomendasi 1. Diseminasi mengenai R to P perlu diperluas dan dapat dimulai dari organisasi−organisasi antar pemerintah yang bersifat regional. Dengan demikian prinsip R to P dapat diterima secara universal dalam praktek hukum internasional. 2. Keberadaan prinsip Responsibility to Protect sebagai norma dalam hukum internasional perlu ditindaklanjuti dengan merancang aturan hukum mengenai prinsip ini dalam bentuk dokumen internasional berupa kovenan yang memiliki kekuatan hukum sehingga harmonisasi serta unifikasi hukum internasional berkaitan dengan R to P dapat terwujud.