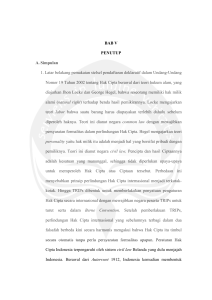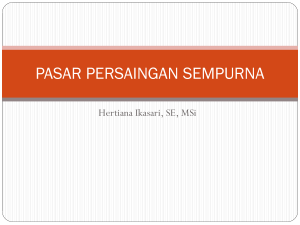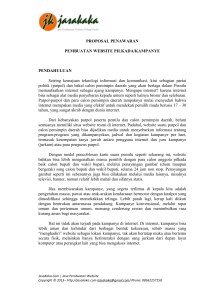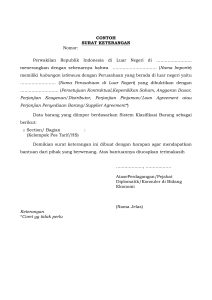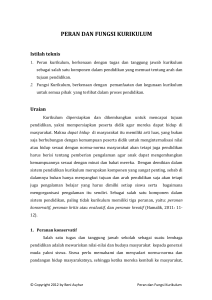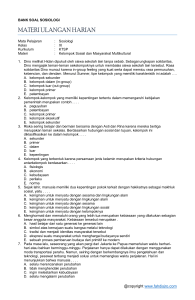Sejarah dan Politik - USU Institutional Repository
advertisement

SEJARAH DAN POLITIK HUKUM HAK CIPTA OLEH : Dr. H. OK. Saidin, SH, M.Hum Dengan Kata Pengantar : Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LL.M, Ph.D PENERBIT : PT. RAJAGRAFINDO PERSADA JAKARTA 2016 19 20 Buku ini didedikasikan untuk Bangsa, Negara dan Tanah air Indonesia. Jangan pernah berhenti mencintai negara dan bangsa ini, akan tetapi jangan juga pernah berhenti memikirkan dan berbuat untuk kebaikan negeri dan bangsa ini, agar tetap utuh ditengah kebhinnekaan, tegak berdiri kokoh, bermarwah dan berdaulat sejajar dengan keberadaan bangsa-bangsa lain. (OK. Saidin, Maret 2016). 21 KATA PENGANTAR PROF. HIKAMAHANTO JUWANA, SH, LLM, PHd. Puji dan syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat Rahmat, Karunia dan nikmat kesehatan serta limpahan berbagai kenikmatan lainnya hingga kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari sebagai wujud pengabdian kita kepadaNya. Selawat beriring salam ke haribaan junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW atas risalah kerasulan yang telah disampaikannya kepada kita ummatnya, semoga di yaumil akhir kelak kita semua mendapat safa’at darinya , Aamin. Buku yang terhidang di hadapan pembaca ini adalah semula disertasi yang ditulis oleh Saudara OK.Sadin yang dipertahankan di depan sidang terbuka senat Guru Besar Universitas Sumatera Utara pada tanggal 17 Desember 2013 dan meraih predikat lulus “dengan pujian”. Selaku Promotor tentu saja saya sangat bangga atas capaian Saudara OK.Saidin menulis sebuah karya ilmiah dalam bidang “Ilmu hukum” dengan pendekatan sejarah dan politik hukum. Meneliti atau mempelajari hukum dari perspektif sejarah dan politik adalah sebuah paradigma yang sangat langka dalam studi ilmu hukum. Sedikit sekali para ilmuwan dalam bidang hukum yang memiliki keberanian untuk masuk ke ranah itu. Ranah ilmiah dalam kajian hukum yang menggunakan atau memanfaatkan teori, konsep dan metode ilmu-ilmu sosial. Namun demikian dengan memiliki talenta menulis yang sangat baik, saudara OK.Saidin akhirnya dapat menyelesaikan disertasinya tepat waktu dan berhasil pula dipertahankan dengan predikat yang sangat membanggakan. Ketika memimpin ujian promosi doctor saudara OK.Saidin, dalam sambutan saya, saya mengatakan Universitas Sumatera Utara cukup berani menentukan syarat bahwa seorang baru boleh mengikuti ujian promosi doctor jika telah memiliki tulisan ilmiah yang dimuat dalam jurnal Internasional. Saat itu saudara OK. Saidin telah menyanggupi itu di mana tulisan beliau telah ”accepted” pada sebuah International Journal, walaupun kemudian harus menunggu beberapa waktu tulisan itu baru dapat dipublikasikan. Namun itu membuktikan kemampuan talenta menulis saudara OK.Saidin tidak diragukan lagi. Pada bulan Juli tahun 2015, akhirnya tulisan beliau dengan judul “Transplantation of Foreign Law into Indonesian Copyright Law : The Victory of Capitalism Ideology on Pancasila Ideology” dipublikasikan dalam Journal of Intellectual Property Rights, terbitan National Intitute of Science Communication And Information 22 Resources, CSIR, New Delhi, India pada edisi July 2015. Sebuah Journal yang masuk dalam indeks International Journal (SCOPUS) dan tentu saja itu sebuah prestasi akademik yang patut diapresiasi. Talenta saudara OK.Saidin dalam menulis memang telah terlatih sejak beliau jadi mahasiswa, banyak tulisan beliau yang dipublikasi di media lokal dan nasional. Di antara tulisan beliau yang telah diterbitkan sejak tahun 1995 adalah buku teks (Text Books) denghan judul “Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) yang diterbitkan oleh PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta sebuah penerbit buku-buku Perguruan Tinggi yang juga memiliki reputasi nasional dan Internasional. Buku itu sekarang ini telah mengalami cetak ulang sebanyak 9 (sembilan) kali dan menjadi buku bacaan wajib bagi mahasiswa yang ingin mendalami bidang hukum Hak Kekayaan Intelektual. Oleh karena itu tidaklah terlalu berlebihan jika saya sampaikan dalam “Kata Pengantar” ini buku yang terhidang di hadapan pembaca ini adalah sebuah karya OK.Saidin yang meskipun semula adalah sebuah disertasi tapi dengan kemampuan talenta menulisnya telah berubah menjadi sumber informasi ilmiah yang lebih mudah dicerna dan difahami. Perbedaannya dengan disertasi sebelum menjadi buku seperti ini adalah, dalam buku ini undang-undang hak cipta yang menjadi obyek kajiannya telah menampilkan UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 yang ketika disertasi itu ditulis UU yang disebut terakhir ini belum disyahkan. Dengan menggunakan bahasa yang lugas serta menggunakan sumber ilmiah yang akurat buku ini menjadi penting untuk dibaca oleh siapapun yang berminat dalam bidang kajian Sejarah dan Politik Hukum. Sekalipun OK.Saidin menjadikan “UU Hak Cipta” sebagai obyek kajiannya, tetapi ia hanya menempatkan undang-undang itu sebagai instrumen penelitian sebagai salah satu bidang hukum yang menjadi obyek pengamatannya, yang sesungguhnya terjadi juga dalam bidang-bidang hukum yang lain dalam pilihan politik (hukum) legislasi nasional. Lebih dari itu sebenarnya saudara OK.Saidin ingin mengajak kita semua melalui studi sejarah dan politik hukum untuk melihat ke masa lampau guna merumuskan pilihan-pilihan politik hukum ke depan, agar hukum Indonesia kelak di kemudian hari benar-benar sesuai dengan cita-cita kemerdekaan, sesuai dengan landasan ideologi Pancasila, sesuai landasan juridis UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui Kebhinnekaan dan berada dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum yang ditawarkan oleh OK.Saidin dalam tulisannya ini adalah, hukum yang berada dalam 23 ruang waktu (sejarah) dan ruang sosial (politik) yang bersumber dari the original paradigmatic values of Indonesian culture and society. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada saudara OK.Saidin. Selamat membaca! Jakarta, 5 Januari 2016 Prof. Hikmahanto Juwana, LLM, PhD. 24 UCAPAN TERIMA KASIH Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin, semua pujian hanya untukMu ya Allah, Tuhan yang maha Pengasih lagi maha Penyayang. Penguasa dan Pencipta alam semesta beserta semua isinya, pemilik Ilmu Pengetahuan yang tidak pernah tidur, mengetahui yang nyata dan yang tersembunyi di hati manusia. Salawat serta Salam kepada Muhammad Rasulallah Salallahu ‘Alaihi Wassallam, Allahumma Sholli ‘ala Muhammad wa ala ‘alihi wasallam. Penyampai risalah, pembawa pesan Allah untuk manusia selaku khalifatul fil’ard yang diberi tugas untuk memakmurkan bumi dan langit dengan segala isinya. Pembawa pesan keadilan (‘adl) dan pesan keilmuan (‘ilm), dua kata yang terbanyak disebut dalam AlQur’an setelah kata “Allah” Buku yang terhidang di hadapan pembaca dengan judul “Hukum Dalam Ruang Sosial Tinjauan Terhadap Undang-undang Hak Cipta Indonesia” ini adalah semula merupakan disertasi penulis yang dipertahankan di hadapan sidang senat terbuka Universitas Sumatera Utara pada tanggal 13 Desember 2013 di bawah wibawa Rektor Universitas Sumatera Utara, Promotor dan Kopromotor serta penguji yang naskahnya terhidang di hadapan Tuan dan Puan adalah tidak lebih dari segelintir ilmu pengetahuan yang teramat sedikit, ibarat stetes air di tengah samudera luas atau sebutir pasir di tengah gurun sahara jika dibandingkan dengan pengetahuan Allah SWT. Karena itu kepadaNya jualah kami berserah diri dan memohon ampun atas “kedhoifan” kami selaku manusia untuk menawarkan sebuah pengetahuan yang mungkin masih jauh dari kebenaran Ilahiyah. Tidaklah mudah bagi kami untuk menulis sebuah disertasi hukum, di tengah situasi negara yang penuh dengan ketidak pastian. Hiruk pikuk politik, kesemerawutan penegakan hukum, ketimpangan pendistribusian ekonomi negara, pelayanan birokrasi yang masih terkesan lamban, legislatif yang dibayar mahal tapi sedikit hasilnya yang berguna bagi negara, aparat penegak hukum yang mendagangkan hukum, dan di mana-mana instansi syarat dengan praktek transaksional untuk tiap-tiap urusan pelayanan umum, sistem otonomi daerah yang hanya memindahkan korupsi yang selama ini tersentralisasi di Jakarta kini beralih ke daerah, reformasi yang hanya menggantikan rezim koruptor lama dengan rezim koruptor baru dan bertumpuk-tumpuk masalah sosial, politik dan hukum yang belum terselesaikan. 25 Untuk memilih judul disertasi saja menimbulkan pergulatan pemikiran internal antara apa yang kami pikirkan dengan apa sesunguhnya yang sedang kami rasakan. Akan tetapi selaku akademisi untuk sebuah tanggung jawab intelektual tidaklah patut untuk tidak memberikan sumbangsih ilmiah bagi upaya memecahkan persoalan yang sedang mengitari bangsa ini. Beruntung ketika tahun1986 pada saat kami duduk pada smester akhir pada perkuliahan di almamater ini, persoalan hak cipta menjadi topik pembahasan yang hangat. Diawali dari kasus pembajakan lagu-lagu Bob Geldof, oleh berbagai produser rekaman illegal di negeri ini mengilhami kami untuk menulis skripsi dengan memilih topik bahasan tentang hak cipta. Naskah skripsi pun setelah selesai diuji selang beberapa lama kemudian dicetak oleh penerbit Rajawali di Jakarta dan kemudian menjadi bacaan wajib dalam kurikulum pendidikan hukum untuk mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual yang kala itu masih langka diajarkan di bebarapa universitas di Indonesia, bahkan di Fakultas Hukum USU pada waktu itu mata kuliah itu belum ada dalam kurikulum pendidikan. Buku ini membawah berkah luar biasa dalam kehidupan kami, karena buku itu menjadi referensi yang sangat langka dan selama 4 tahun pertama terus menerus dicetak ulang, dan honorarium inilah yang mengantarkan saya dan isteri menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah. Tidak itu saja, buku ini juga telah mengatarkan kami menjadi pembicara di berbagai pertemuan ilmiah, puncaknya kami mendapat kesempatan mengikuti pendidikan di Tokyo atas kerjasama Japan Patent Office dengan Japan Institute of Invention and Innovation (JIII) pada bulan Pebruari Pebruari tahun 2002 dan kesempatan untuk mengikuti Shot Courses di University Mumbai dan Institut Information Technology di Mumbai India pada tahun berikutnya. Tahun 1995 saya berhasil menyelesaikan pendidikan Program Pasca Sarjana (S2) dan saya bermaksud melanjutkan studi S3, akan tetapi saya kurang beruntung, saya tak dapat memulai studi S3 pada tahun itu, dikarenakan berbagai faktor, tapi proposal penelitian untuk disertasi sudah kami siapkan pada tahun itu.Beberapa tahun kemudian barulah ada kelonggaran waktu kami untuk dapat kembali mengikuti program pendidikan S3. Akan tetapi sesuatu yang sangat mengejutkan proposal penelitian 15 tahun yang lalu itu, belum pernah terjawab oleh kalangan akademisi yang menggeluti dunia hukum. Padahal selama kurun waktu itu tidak kurang dari 15 orang menyelesaikan studi S3 dengan memilih topik Hak kekayaan Intelektual. 26 Selama kurun waktu 15 tahun itu, selama itu pula kami mengamati dari waktu ke waktu perubahan UU Hak Cipta Nasional dan terus menerus menuliskannya di berbagai media dan journal. Terus menerus menjadi pemakalah di berbagai seminar lokal dan nasional untuk topik yang sama. Satu kali kami mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemakalah pada sebuah seminar di University Malaya dengan tema perbandingan hukum Hak Kekayaan Intelektual Malaysia dan Indonesia Atas jasa baik Prof.Dr.Djohar Arifin Husein dan Prof.Dr.Mohd Razali Agus dari University Malaya kami dapat mendalami tentang seluk beluk hukum Hak Kekayaan Intelektual di Malaysia, menyusul seminar berikutnya di selenggarakan di University Kebangsaan Malaysia di bawah panduan Prof Dr. Sakinah. Paling tidak pengalaman itu menjadi langkah awal untuk menyingkap sebuah pertanyaan besar, apakah hukum Hak Kekayaan Intelektual yang berasal dari peradaban Hukum Barat itu “berterima baik” di belahan bumi Asia dengan peradaban Asia. Untuk kasus Indonesia pertanyaan yang diajukan tetap sama, dengan usulan proposal dalam disertasi ini, yakni ; mengapa UU Hak Cipta Nasional begitu kering dari nuansa ideologi Pancasila dan syarat dengan muatan ideologi Asing. Sudah sebegitu beratkan beban bangsa ini, hingga tak mampu lagi dipikul oleh anak bangsa ini, sehingga harus menggadaikan hal yang paling azasi dalam kehidupan bernegara dan berbangsa yakni Pancasila. Atau Pancasila ini perlu diberi tafsir ulang untuk menyahuti tuntutan globalisasi yang sedang menyeruak di seluruh belahan dunia ini? Itu adalah pertanyaan yang menantang secara akademis yang memerlukan jawaban tidak hanya dalam tataran empiris akan tetapi juga dalam tataran filosofis. Tantangan dalam babakan berikutnya adalah, jika tulisan ini dimulai, apa judul yang tepat, bagaimana metodologinya, apakah harus mengikuti metode konvensional atau melakukan terobosan-terobosan baru ? Sebab akar persoalannnya ada pada kebijakan negara, ada pada pilihan politik hukum negara, ada hubungannya dengan tekanan politik Internasional, ada hubungannya dengan ketergantungan hutang luar negeri, ada hubungannya dengan lembaga keuangan Internasional seperti International Monetary Fund dan World Bank, ada kaitannya dengan budaya birokrasi, budaya penegakan hukum dan budaya masyarakat. Bagaimana semua persoalan ini terjawab secara filosofis dan mendasar, sehingga dapat dilukiskan secara utuh realitas sosial hukum yang mengitari keberlakuan hukum itu dalam masyarakat ? Langkah penulisan disertasi ini tidak hanya cukup dengan sebuah semangat atau keberanian, tapi juga penulisan disertasi ini diawali dengan sebuah 27 “kegilaan”. Toch sebuah disertasi tidak mesti dibaca oleh semua orang, hanya kalangan tertentu dan orang-orang yang dapat memaknai filosofi sebuah tulisan yang dapat kesempatan untuk membacanya. Dengan alasan itulah disertasi ini mulai ditulis dan butir-butir pemikiran mulai mengalir merambah ke seluruh penjuru dan lorong-lorong yang terjal kadang berliku, kadang ada cahaya, kadang penuh kegelapan. Betapa tidak dengan pendekatan sejarah, dan pisau analisis politik hukum, perbandingan hukum, sosiologi hukum dan antropologi hukum tak satupun lagi terlihat adanya gagasan cita-cita hukum nasional yang diterapkan oleh lembaga pembuat undang-undang ketika melakukan transplantasi hukum asing dalam pembentukan UU hak Cipta Nasional. Puncaknya ideologi Pancasila sebagai abstraksi dari the original paradigmatic values of Indonesian culture, mati di tangan anak bangsa sendiri. Paragraf demi paragraf disertasi ini ditulis, diurai dan dianalisis. Ketika sampai pada paragraf yang berjudul pergeseran nilai filosofi, pikiran kami melayang ke sosok Guru Besar Fakultas Hukum USU, Prof.Mahadi, pendiri Fakultas Hukum USU, yang dengan bahasa yang sederhana menuturkan tentang peranan nilai-nilai filosofis sebagai azas hukum dalam pembentukan norma hukum. Teringat pula bagaimana sosok beliau pada tahun 1986 itu membimbing kami dalam penulisan skripsi yang kelak di kemudian hari mengilhami penulisan disertasi ini, oleh karena itu beliau adalah sosok yang teramat pantas untuk kami sampaikan terima kasih, semoga ilmu yang beliau ajarkan menjadi cahaya penerang beliau di alam barzah, Aamin ya Rabbal Alamin. Begitu juga ketika tulisan ini sampai pada paragraf tentang hukum benda, yang menempatkan hak cipta sebagai benda tidak berwujud dan sejumlah azas hukum benda yang melekat pada hak cipta, pikiran kami menerawang ke seorang sosok intelektual hukum yang dalam lapangan hukum perdata menurut kami belum ada tandingannya, seorang ibu yang dengan kelembutan dan kesantunannya telah banyak mewarnai perjalanan intelektual kami, karena itu tak ada kata yang lebih baik yang dapat menampung semua jasa beliau kecuali ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya untuk sosok Ibu kami Prof.Dr.Mariam Darus Badrulzaman,SH. Ketika, suatu hari saya mendapat pesan telepon dari Prof.Dr.M.Solly Lubis, SH agar kami datang menghadap beliau. Kesempatan pertama hadir di ruangan beliau, saya disodorkan proposal yang saya ajukan 12 tahun yang lalu dan masih tersimpan di arsip beliau. Beliau mengatakan teruskanlah tulisan ini dan ini akan menjadi 28 sebuah studi dengan pendekatan yang langka. Pada waktu itu juga beliau menyatakan kesediaannya untuk menjadi Co-Promotor dalam penulisan disertasi ini. Tidak itu saja beliau mengizinkan kami untuk menggunakan anlisis politik hukum dengan menggunakan teori sisnas sebuah teori original milik beliau. Hukum tak mungkin dapat dikeluarkan dari sistem nasional dan sebagai suatu sistem keberadaan dan bekerjanya hukum dalam sistem sosial (nasional) akan dipengaruhi sub sistem sosial lainnya. Karena itu sebuah keharusan dan kepatutan akademik dengan ketulusan yang dalam kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau, semoga Allah tetap mengucurkan Rahmat kesehatan agar beliau dapat terus menerus mengabdikan ilmunya di Almamater kita tercinta ini.Aamin Ya Rabbal Alamin. Mungkin karir akademis kami tidak akan sampai pada apa yang yang kami peroleh hari ini, jika tidak ada sosok seorang yang terus menerus memaksa kami untuk menggeluti dunia ilmiah, beliau adalah OK.Chairuddin, SH yang pertama kali meminta saya untuk tampil di depan kelas mengajarkan teori Struktural Fungsional dari Robert K.Merton, dan Teori Interaksionis Simbolik dari Emile Durkheim. Ajarkan kepada mahasiswa bagimana orang pada saat lampu merah yang semula dia telah berhenti, akan tetapi karena kenderaan di sebelahnya menerobos lampu merah itu lalu kemudian dia ikut-ikutan menerobos lampu merah itu. Pelanggaran hukum terjadi karena secara simbolik prilaku orang-orang akan berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya. Sejak hari itu, saya terus dipercayakan beliau untuk berdiri di depan kelas dan menggantikan beliau sebagai pembicara di berbagai forum seminar. Oleh karena itu untuk semua jasa dan kebaikan beliau kami sekeluarga mengucapkan terima kasih yang setingginya, semoga ini menjadi amal baik yang tidak pernah terputus. Ketika menjabat wakil ketua Ikatan Mahasiswa Perdata, Prof. Syamsul Bahri, SH menjabat Ketua Jurusan Hukum Perdata. Selang beberapa bulan beliau terpilih menjadi Pembantu Rektor II dan kamipun baru beberapa bulan menyelesaikan studi S1, namun sudah menjadi Asisten Dosen (yang istilahnya waktu dosen lokal dalam arti belum pegawai negeri). Sebuah kenangan yang tak terlupakan ketika Prof. Syamsul Bahri,SH atas permintaan Prof.Mahadi saya diusulkan beliau untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri (staf pengajar). Tanpa uluran tangan dan kemurahan hati beliau, mungkin kami tak sampai pada forum yang sangat berbahagia pada hari ini. Oleh karena kami persembahkan ucapan terima kasih kami yang setinggi-tinginya atas semua jasa dan kebaikan hati beliau. Semoga Allah tetap melimpahkan 29 nikmat kesehatan dan umur yang panjang kepada beliau, Aamin ya Rabbal Alamin. Sebuah cambuk sering bermakna kekerasan, tapi cambuk kali ini justeru penuh kelembutan. Betapa tidak sosok seorang Pak Cik yang kami selalu panggil “Om Dob” di keluarga kami, selalu saja menanyakan, “kapan lagi awak selesaikan sekolah tu?” Inilah cambuk kelembutan dari sosok Om kami Prof.Chainur Arrasjid, SH. Pertanyaan itu sekali waktu membakar semangat kami, tapi di waktu yang lain membuat hati kami kecut, kalau-kalau nanti berjumpa dalam pertemuan keluarga atau bertemu dalam urusan Kampus Universitas Amir Hamzah di mana beliau sebagai ketua pembina dan saya sebagai Sekjen yayasan. Tapi apapun itu setelah hari ini pertanyaan om yang sama takkan pernah muncul lagi, Terimalah ucapan terima kasih ananda atas segala cemeti namun penuh dukungan hingga ananda dapat menyelesaikan jenjang pendidikan tertinggi di almamater ini. Tiap kali bertemu selalu dengan senyum tulus, urusan dengan saya tidak terlalu besar kecuali mengantarkan beliau menjadi penumpang istemewa pada saat-saat tak terduga dan berkebetulan dari Fakultas Hukum ke rumah beliau yang atap rumahnya terlihat jelas dari Fakultas Hukum. Tapi hati saya selalu berbunga-bunga kalau berdiskusi dengan beliau. Donald Black adalah tokoh sosiologi hukum yang selalu beliau kutip dalam kuliah. Tapi bukan itu yang membuat hati saya berbunga, dia selalu memanggil saya dengan sebutan “richt man” alias Orang Kaya. Sosok beliau yang familier dan ketika disertasi ini sampai pada paragraf yang harus mengutip Donald Black, pikiran saya kembali menerawang kepada sosok Prof.Moh.Abduh yang dalam banyak hal mengilhami pendekatan sosiologis dalam tulisan ini. Tentu hanya ucapan Terima Kasih yang dapat kami persembahkan untuk beliau, semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan kepada Professor sekeluarga. Aaamin ya rabbal Alamin. Tentu pada tiap-tiap pertemuan menghadirkan banyak kesan yang beragam. Tapi kesan pada sosok Guru Besar yang Charming ini tak bisa kami lupakan. Senyum ketulusannya mewarnai kejujuran intellektual siapapun yang akan berdiskusi dengan beliau. Prof Sanwani Nasution adalah sosok yang tak mudah untuk kami lupakan. Beliaulah Dekan penanda tangan ijazah S1 kami dan beliau yang dalam berbagai kesempatan bersama-sama dengan Alm. Kkd Prof.Hasnil Basri Siregar yang memberikan support atas berbagai kegiatan akademik yang melibatkan mahasiswa dan pilihan jatuh pada kami dan pada zamannya kami dikukuhkan sebagai Mahasiswa Teladan. Terima Kasih Professor, 30 semoga semua ini menjadi catatan amal baik yang akan menjadi kenangan sepanjang masa. Pada suatu ketika saya dan kakanda M. Husni, SH,M.Hum. mendapat kesempatan mengikuti shot courses di PAU-UGM. Di sana banyak hal yang baru yang kami temui. Bersentuhan pemikiran mulai dari Ekonom, Prof.Mubyarto, Sosiolog Prof.Nasikun, Sejarawan, Prof.Sartono Kartodirjo, Prof. Ichlasul Amal, Prof. Masri Singarimbun, Prof.Kuntowijoyo sampai pada William Liddle. Tiga bulan melakukan penelitian bersama di desa-desa di wilayah Yogyakarta, membuat kami semakin faham bahwa hukum tak dapat didekati dari satu perspektif keilmuan saja, tapi perlu pendekatan multi paradigma. Pemahaman semacam itu semakin menggelora di jiwa kami, manakala kami mengikuti berbagai pelatihan yang menggunakan penedekatan ilmu sosial dalam kajian hukum, selama kurun waktu Tahun 1990-2000. Berulang kali kami merajut pemikiran dari para tutor, antara lain Ibu Prof. T.O. Ihromi, Prof.Satjipto Rahardjo dan Prof Soetandyo Wignjosoebroto. Sebagai resultant dari semua studi-studi yang kami ikuti itu, terjelma dalam disertasi ini, karena itu disertasi ini melampaui dari tradisi penelitian ilmu hukum yang dianut secara ketat selama ini di berbagai Fakultas Hukum di Indonesia. Oleh karena itu kesempatan ini, kami gunakan untuk mengucapkan terima kasih kepada semua “Guru Besar” yang berjasa dalam mengukir alur pikir kami terhadap studi hukum. Tentu, keberuntungan semacam itu tak dapat diperoleh oleh setiap insan, saya hanyalah satu dari sekian banyak staf pengajar yang dapat keberuntungan itu, manakala Promotor dan Co Promotor telah memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada kami untuk menggunakan pendekatan yang keluar dari tradisi kajian ilmu hukum selama ini. Pisau analiis, politik hukum, sejarah hukum, sosiologi hukum dan perbandingan hukum yang secara serentak diterapkan dalam penelitian ini dan itu tidak akan dapat diterapkan tanpa bimbingan dan arahan dari Promotor dan Co Promotor yang sangat arif. Di bawah kewibawaan Prof. Hikmahanto Juwana,SH. LL.M,Ph.D. Prof.Dr. M.Solly Lubis, SH dan Prof.Dr.Tan Kamello,SH,MS selaku Promotor dan Co Promotor, kami merasakan sebuah kebebasan ilmiah, kebebasan untuk berkreativitas, kebebasan berfikir dan mengeluarkan pendapat menjadi suluh dan penerang dalam kami menyelesaikan disertasi ini, sehingga kami benar-benar terayomi dan nyaman dalam menyelesaikan penelitian ini. Untuk itu tak ada kata yang tepat untuk mengungkapkan dan meluapkan rasa kegembiraan dan rasa syukur kami, kecuali ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 31 Professor bertiga, semoga Allah membalas semua amal kebaikan yang telah Professor lakukan buat kemajuan kami khususnya serta kemajuan Universitasa Sumatera Utara pada umumnya. Aamin ya Rabbal ‘alamin. Para tim Penguji adalah para kritikus pertama yang menyentakkan kengangkuhan dan kesombongan intelektual kami. Betapa tidak, Referensi dan data yang kami peroleh selalu menguatkan asumsi kami, pada hal ada data dan informasi lain yang berbeda dengan itu. Sebuah kritik tetaplah diperlukan untuk penyeimbang, dan saya berbesar hati untuk menerima semua kritik itu. Tentu saja hasilnya adalah mengarah pada sebuah perbaikan untuk menuju kesempurnaan. Itulah yang terus menerus saya peroleh dari Tim Penguji sejak tahap kolokium hingga ujian terbuka pada hari ini. Untuk itu teramat pantas dan patut kiranya kami menyampai terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. M.Hawin,SH,LL.M,Ph.D dan Prof. Dr. Suhaidi, SH,MH dan Prof.Dr.Ningrum Natasya Sirait, SH, MLI yang tidak sedikit memberi sumbangsih bagi penyempurnaan tulisan ini. Tiap waktu mulai saat akan mengikuti jenjang perkuliahan sampai pada tahap-tahap menjelang ujian, saya terus menerus “mengganggu” Professor yang satu ini. Betapa tidak, mulai dari urusan rekomendasi untuk mendapatlan izin Rektor sampai dengan konsultasi siapa yang akan menjadi Promotor dan Co Promotor dan terlebih-lebih lagi dalam penentuan tanggal ujian pada tiap-tiap tahapan. Karena harus diakui tidaklah mudah untuk menyesuaikan waktu tiap-tiap waktu Promotor dan penguji yang kita faham memiliki kesibukan yang luar biasa. Tentu saja untuk mendesain seluruh rangkaian administratif ini diuperluklan kewibawaan, dan atas wibawa Prof.Dr. Runtung Sitepu SH.M.Hum, baik dalam kapasitasnya sebagai Dekan maupun sebagai kolega dan sahabat semua itu berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Saya berhutang budi kepada beliau dan bak kata pepatah melayu, “hutang emas dapat dibayar, hutang budi di bawa mati” Saya kembalikan kepada Allah SWT atas semua kebaikan hati Professor, semoga Professor sekeluarga mendapat Ridho dan Rahmat dari Allah SWT dalam menjalankan kepemimpinannnya hari ini dan masa yang akan datang, Aamin ya Rabbal Alamin. Tidak sedikit juga sumbangsih ilmiah dari para dosen dan staf pengajar selama mengikuti jenjang pendidikan S3 ini, Prof.Dr.Bismar Nasution, SH,MH, adalah satu dari sekian banyak nama-nama yang harus kami beri apresiasi. Hari-hari pertama kami memasuki jenjang pendidikan S3 adalah hari-hari di mana setiap waktu saya mengganggu dan mengusik jam-jam istirahat beliau. Mulai dari meminjam buku- 32 buku sampai pada meminta arahan untuk penyusunan propopsal yang baik. Tentu saja hasilnya seperti yang terangkai dalam disertasi ini. Terima kasih kakanda, semoga Allah tetap memberikan hidayah dan kekuatan kepada Kakanda sekeluarga dan dapat terus melahirkan kader-kader akademik yang berkualitas. Sahabat-sahabat dan kolega kami, Prof.Budiman Ginting, Prof.Dr. M.Yamin Lubis,SH. Prof.Dr.Alvi Syahrin,SH,MS, Prof.Dr. Sunarmi,SH,MH, Prof. Dr. Syafruddin Kalo, SH, M.Hum, Prof. Dr. Suwarto, SH,MH, Prof. H. Syamsul Arifin,SH,MH, Dr.Mahmul Siregar, SH,M.Hum, Dr.Pendastaren Tarigan, SH, MS, Dr. Madiasa Ablisar, SH,MS, Dr. Faisal Akbar Nasution, SH,M.Hum, Dr. Hasyim Purba, SH, M,Hum, Dr. M. Hamdan,SH, MH, Dr. T. Keizerina Devi A.S.H.C.N, M.Hum, Dr. Dedi Harianto, SH, M.Hum, Dr.Mirza Nasution, SH, M.Hum, Dr. Jelly Leviza, SH, M.Hum, Dr. Mahmud Mulyadi, SH, M.Hum, Dr. Agusmidah, SH, M.Hum, Dr. Marlina, SH, M.Hum, Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum, Dr. Idha Aprilyana, SH, M. Hum, adalah sederetan nama-nama yang dalam berbagai kesempatan secara sadar dan tanpa sadar telah mewarnai perjalanan akademis kami di almamater yang kita cintai ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi langkah kaki kita dalam menapak karir sebagai pionir dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada suatu masa selepas dari mengikuti berbagai pelatihan tentang peranan ilmu-ilmu sosial dalam kajian hukum, kami bermaksud untuk mendirikan pusat kajian hukum dan masyarakat. Bersama-sama rekan-rekan pengajar mata kuliah sosiologi dan antropologi kami mendirikan Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat dan salah satu aktivitasnya adanya menggelar diskusi mingguan. Kami bersihkan satu ruangan yang pada waktu itu menjadi sarang walet di bangunan Gedung Judicium Fakultas Hukum USU. Babak berikutnya kami mengelola satu jurnal ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial yang kami beri nama “Mahadi” yang diterbitkan oleh KSHM. Kami juga menerbitkan buku-buku karya dosen Fakultas Hukum USU dan Fakultas Hukum Universitas swasta lainnya di Medan. Kami mendapat dukungan terbesar ketika itu dari sosok yang bersahaja yaitu T.Mansyurdin, SH, betapapaun juga lembaga yang kami dirikan itu sampai hari ini masih eksis dan terus menerbitkan karya-karya ilmiah dosen Fakultas Hukum USU dan itu membawa kami pada ke’arifan ilmiah yang mempengaruhi cara berpikir dan cara pandang kami pada hari ini dan warna itu terlihat jelas dalam analisis kami dalam disertasi ini. Untuk itu kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua sahabat yang terlibat di dalam forum ini, untuk kami sebutkan beberapa 33 nama; T.Mansyurdin, Dr.Jusmadi Sikumbang, SH.MH. Erwin Adhanto, Edy Zulham, M.Husni, SH.M.H dan Dr.Edy Ikhsan. Khusus terhadap Dr. Edy Ikhsan,SH,MA sahabat dalam suka dan duka, selama kurun waktu 32 tahun banyak peristiwa yang kami lalui bersama. Rekam jejak persahabatan ini tak dapat diuraikan dalam satu buku tebal. Mulai dari mengenderai kenderaan roda 2 dari Medan sampai P.Siantar di malam hari dalam keadaan mati lampu, memancing hingga sampan hampir karam, sampai pada menelusuri dokumendokumen dan arsip-arsip tua di Den Haag dan menunaikan ibadah umroh bersama. Lebih dari itu, pergulatan pemikiran dan tunas-tunas intelektual akademik terbangun sejak kami bersama-sama dalam organisasi HMI lalu kemudian bersama memilih menjadi “guru” sebagai basic perjuangan. Di kampus kami mendirikan pusat kajian hukum dan ilmu-ilmu sosial, di luar kampus kami membangun berbagai aktivitas di bawah LSM. Tak ada yang lepas dari pantauan kami dan tak ada yang lepas pula dari diskusi kami, karena itu perjalanan akademis yang kami lalui hari ini tak lebih dari apa yang pernah kami pikirkan dan lalui bersama, semoga persahabatan ini kekal selamanya di dunia dan di akhirat kelak. Aamin ya Rabbal Alamin. Perjalanan penyelesaian disertasi ini ada juga andil dari Bu Lola, Bu Ninin dan Kak Ani, tanpa dukungan mereka agaknya tak mungkin rasanya kami dapat berdiri di sini pada hari ini. Ibu Farida Runtung, Ibu Mimi Suhaidi, adalah dua nama untuk menyebutkan dari sekian banyak sahabat isteri saya yang memberikan andil dan dukungan moril bagi kami sekeluarga, untuk itu kami ucapkan terima kasih. Kenangan yang tak mungkin terhapus adalah dari sosok seorang abang yang dalam berbagai aktivitas ilmiah di kampus tetap mengajak kami berdiskusi dan memberikan kesempatan kepada kami. Sebuah nepotisme ilmiah yang luar biasa ketika saya diutus untuk mengikuti lomba karya ilmiah di UNSRI Palembang ketika kami duduk di semester akhir di Fakultas Hukum. Dalam jabatannya selaku PD III, Prof.Hasnil Basri Siregar, SH mengutus kami untuk mewakili Fakultas Hukum USU, hasilnya tentu tidak mengecewakan beliau kami pulang dengan membawa piagam dan tropi Juara II, karena lazimnya Juara I harus dimenangkan oleh Tuan Rumah. Selaku tokoh HMI, almarhum terus menyemangati kami yang dengan penuh kegilaan kami menghabiskan waktu di organisasi mahasiswa itu dan dilanjutkan di organisasi berikutnya yakni KAHMI setelah menyelesaikan studi S1. Kakanda yang satu ini telah banyak memberikan spirit, sehingga jika diuraikan tak cukup dalam satu alinea, begitupun dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang setingginya kepada beliau dan 34 semoga Allah SWT melapangkannya di alam barzah. Allahumma firlahu warhamhu wa ‘afihi fa’fu’anhu. Untuk kak Oma kami menaruh hutang budi, begitu juga untuk kak Icik , terima kasih kepada kakak berdua. Do’a yang sama untuk Almarhum.Prof.M.Daud, SH, Prof. Dr. Bachtiar Agus Salim, Prof. Dr. Mustafa Siregar, H.Miharza, Pangoloan Nainggolan, Syahruddin Husein, Darmansyah Hasibuan, Djamhir, Syahmenan, Zulkarnain Mahfudz, Burhan Aziddin, Abdul Azis, SH, Aminah Azis, SH, Hoesni, SH, Syamsiar Yulia, dan seluruh guru-guru kami yang telah mendahului kita, Allahummaghfirlahum Warhamhum Wa’afihi Wa’fu’anhum. Ketika masa-masa awal kuliah di almamater ini hingga selesai dan kemudian menjadi dosen di Fakultas Hukum USU, banyak peranan abang-abang senior yang berkesan dan berpengaruh dalam kehidupan akademis kami.Bang Ong, Bang Hayat, Kak Adek (Sinta Uli, SH,M.Hum), kak Adek (Rabiatul), bang Asmin, bang Tiar, Kak Irul, bang Siba, bang Sidik, bang Azwar, bang Husni adalah mereka-mereka di antaranya. Sulit rasanya memperifikasi peran beliau, tapi yang kami tahu adalah mereka punya andil tersendiri bagi kehidupan akademis kami di almamater ini. Untuk itu terimalah ucapan terima kasih kami. Kolega-kolega seangkatan, Zulkifli Sembiring,SH.,M.Hum. Nurmalawaty.SH.,M.Hum. teman bersenda gurau dalam berbagai kesempatan adalah mereka-mereka yang pantas ikut berbahagia pada hari ini. Adik-adik kelas yang kemudian menjadi kolega kami, Dr.Rosnidar Sembiring,SH,M.Hum. Syamsul Rizal,SH,M.Hum, Afrita Abduh,SH.M.Hum. Dr.Mahmul Nasution,SH,M,Hum adalah juga adikadik manis yang baik hati yang terus menerus memberi semangat, terutama di saat-saat terakhir disertasi ini ditulis kecelakaan kecil telah menimpa kami hingga tangan kanan kami tak dapat difungsikan selama lebih dari enam bulan. Rekan di HMI terutama kakanda Syahruzal Yusuf dan Kkd Faisal Putra, kkd Husni Nasution, SH, CN dan Kakanda Nurdin Lubis, SH, MM dan Kkd Sutiarnoto Ms, SH, M.Hum, adalah mereka-mereka yang telah memberi spirit lebih dari yang seharusnya kami terima. Adik-adik di HMI pun telah memberikan andil yang tidak sedikit dalam pencapaian karir akademis kami, “Yakin Usaha Sampai” karena itu terimalah ucapan terima kasih kami pada organisasi yang pertama kali mengajarkan kami berpidato dan membuat surat. Rekan-rekan di SMA negeri 8 yang hari ini di antaranya telah menempati derajat akademik tertinggi dan hari ini tampil sebagai Co Promotor dan Penguji, yang amat terpelajar Prof Dr.Tan 35 Kamello,SH.MS. dan Prof Dr.SuhaidiSH.M.H, keduanya juga duduk sebagai Ketua dan Sekretaris Program Doktor (S3) FH USU, tentu saja tak sedikit pula andilnya dalam penyelesaian studi kami di Universitas yang kita cintai ini. Untuk itu terimalah ucapan terima kasih kami. Sahabat kami Azhar Tanjung, Anwar Effendi Siregar, Riana Melia Barus, Siti Banina, Wahyuddin, Jufkar, Mishartono, Syahril Sabirin, Israil Surbakti, M. Saidi, Ferisia, Abdul Hakim Harahap, Siti Asmah Lubis, Sarwani, Riadil Akhir Lubis, Eka Riono, Syahruddin Lubis, Junaidi, Khairwansyah Lubis, Paimin, Zainul Arifin, Sunarji dan Rehulina Tarigan, adalah rekan-rekan semasa SMA yang mengukir kenangan indah yang tak terlupakan dan sampai hari ini persahabatan itu terpelihara dengan baik. Do’a kalian semua di sertai rasa empaty yang dalam di saat-saat kami mengalami kedukaan namun dalam saat bersamaan menuntut penyelesaian disertasi ini telah menyemangati kami dalam menyelesaikan studi ini. Rekan-rekan pengurus MABMI, KAHMI , AMPI dan KNPI serta Ikatan keluarga Besar Batu Bara adalah mereka-mereka yang turut memberi andil dalam perjalanan karir akademik kami dan karenanya teramat pantas menerima ucapan terima kasih dari kami. Kawan-kawan di Grup 44, Faris S.Bashel, Said Hamid, M.Yususf, Hakim S.Bashel, A.K.Bashel , wak Alay, Bang Muin dan Bang Malik adalah merekamereka yang secara terus menerus memberi spirit untuk penyelesaian disertasi ini. Hutang budi kami juga tak terputus buat A.K Bashel, Ali Cetin dan Pauline, sahabat di Holland, Turkey dan Prancis yang selain sebagai responden dalam disertasi ini juga mereka-mereka yang siap mengirim buku-buku referensi dari negaranya karena itu terima kasih untuk semua bantuannya. Sahabat-sahabat responden disertasi ini di Kejaksaan, Kepolisian dan Kehakiman yang tak dapat kami rinci satu persatu, tapi kontribusi sahabat-sahabat semua telah memberi warna tersendiri dalam disertasi ini. Adik-adik mahasiswa yang turut dalam menyebarkan kuesioner dalam pengumpulan data disertasi ini, terutama adik-adik yang tergabung dalam HMI, paling tidak kita semua pernah telah menyemai benih ilmiah yang hasilnya akan kita tuai bersama di kemudian hari, karenanya kami berkewajiban menyampaikan terima kasih khusus untuk semua partisipasinya. Sahabat-sahabat dan seluruh karyawan PT.Harfa, PT.Rahmat Alam Sejatera, PT.Mutiara Hijau, serta seluruh pengurus yayasan dan civitas akademika Universitas Amir Hamzah, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi dan kesetiaan kita semua untuk mengelola manajemen perusahaan dan yayasan di saat kami tak dapat melakukan aktivitas penuh di celah-celah kesibukan kami dalam 36 menyusun disertasi ini, tanpa itu semua saya tak akan mampu menyelesaikan studi ini tepat waktu. Kolega di PT.Indo Turk Company, Emin Cinar Bey dan Organ Bey, juga memberi andil dalam perjalanan penulisan disertasi ini, Chok Tasyakkur Abe. Ibu Prof. Dr dr Irma Mahadi dan Prof Dr.T.Silvina Sinar dan Dr.T.Tirhaya Sinar adalah mereka yang sangat berjasa dalam memberikan sumbangan Kepustakaan dalam penyususunan disertasi ini. Saya telah menguras habis seluruh perpustakaan Prof Mahadi atas kemurahan hati Kak Irma, terima kasih kak, Semoga ini menjadi amal baik yang tak terputus dari Almarhum beserta keluarga. Prof Dr.Sayaka di Tokyo University dan Prof Minako Sakai di Melbourne University adalah sahabat-sahabat baik yang terus menerus memberikan informasi berguna bagi penulisan disertasi ini, karenanya teramat pantas kami menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Prof.Kentaro Cikawa dan Prof.Yoshida masing-masing sebagai Chairman pada The Association For Overseas Technical Scholarship (AOTS) dan Vice Chairnan President Japan Institut of Invention an Inovation keduanya di Tokyo adalah orang yang teramat pantas kami berikan apresiasi atas dukungannya dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan perkembangan hukum HKI di kawasan Asia Fasifik dan secara terus tiada henti mengirim journal kepada kami. Tentu saja ini sangat membantu kami, terima kasih untuk semua kebaikan itu. Sultan Deli Mahmud Lamantjitji, Pemangku Sultan Deli Tengku Hamdy Osman Delikhan gelar Tengku Raja Muda Deli, Tengku Husni Osman Deli Khan Gelar Tengku Temenggung Deli, Tengku Fauziddin, Tengku Ismin, Datuq 4 suku, Kepala Urung Serbanyaman, Datuq Syaifi Ichsan gelar Datuq Seri Indera Pahlawan Diraja, Kepala Urung Sepuluh Dua Kuta, Datuq Adil Freddy Haberham, SE gelar Datuq Seri Setia Diraja, Kepala Urung Sukapiring, Datuq Ahmad Fauzi Moeris Al Haj gelar Datuq Seri Indera Asmara, Kepala Urung Senembah Deli, Wan Fahrurozi Baros gelar Kejeruan Senembah Deli adalah merekamereka yang dengan penuh harap dengan iringan do’a untuk capaian akademik kami pada hari ini.Terima kasih kami persembahkan untuk institusi Kesultanan Deli. Alm Tuanku Luckman Sinar Basharsyah II, adalah sosok seorang bangsawan yang memberi kesan dalam perjalan karir kami yang kepemimpinannya dilanjutkan oleh Tuanku Ahmad Tala’ah, Sultan Negeri Serdang, Tuanku dr.Abraham Abdul Djalil Rahmatsyah, Sultan Asahan, Tuanku Azwar Aziz Abdul Djalil Rahmatsyah, Pemangku Adat, Bilah, Panei, Kuwaluh, Kota Pinang, Kerajaan Sambilan Nasapuluh, Konfederasi Batu Bara dan Keluarga Besar Raja 37 Tanah Jawa adalah mereka-mereka yang memberi spirit dan dukungan, betapa pendidikan telah kita pilih sebagai jalur yang tepat untuk mengangkat harkat, martabat dan marwah anak negeri yang terpinggirkan. Hari ini kami akan persembahkan capaian akademik ini untuk seluruh kawula anak negeri ini, semoga karya ini membuka jalan pada anak negeri yang merindukan pencerahan. Sosok Tokoh pendidik dan Tokoh pejuang yang banyak merubah persepsi kami terhadap dunia adalah Prof,Bahauddin Darus, dengan kewibawaan dan istiqomahnya dalam menegakkan perjuangan pembangunan Desa Pantai telah mengantarkan kami pada berbagai pilihan bahwa kepemihakan kepada kaum dhuaffah mustad’affin harus terus menerus menjadi pilihan dan itu juga yang mengantarkan kami pada berbagai kegiatan penelitian di luar kampus bersama-sama dengan Prof.Meneth Ginting dan Prof.Dr.Mochtar Ahmad dari Universitas Riau. Mereka-mereka adalah orang yang berjasa dalam perjalanan karir akademik kami dan karenanya kami berhutang budi, terima kasih untuk semuanya semoga Allah membalas dengan kebaikan yang banyak. Adalah Mak Alm.Hj Dewi binti Muh Buang dan Abah Alm.OK.Moh.Saluji bin OK.Moh.Syarif yang tak sempat menyaksikan perhelatan yang penuh hikmat ini, akan tetapi arwah Mak dan Abah boleh tersenyum untuk apa yang ananda boleh capai hari ini, apapun juga kata yang dipilih tak cukup mampu menampung ungkapan pujipujian untuk Mak dan Abah dan apapun juga yang kami bisa berikan tak cukup mampu membalas semua kebaikan dan pengorbanan yang telah Mak dan Abah berikan untuk kami, kesemua itu hanya kami persembahkan kepada Ilahi Rabbi, semoga Arwah Mak dan Abah senantiasa berada dalam Kemuliaan Allah SWT. Allah hummaghfirli Wali wali dayya warhamhuma kama Rabbayani Shoghiro. Buat Abah Almarhum H.Said Yusuf, Ummi Syarifah Azizah, Ayahanda Alm.Drs. OK. Usman dan Ibunda Dra.Djadidah, serta abang, kakak dan adik-adik tercinta, H.OK.Muchtar, Hj.Dahliah, Alm Syahril, Hj.Nurhayati, Nuraisyah dan Lela Erwany, SS, M.Hum. Abangda Said Fahmi, SE, Ir.Syarifah Syamrah, Syarifah Nurul Huda, Syarifah Zahrani, drg Syarifah Suhaila, Said Fuad dan Said Munzir, SE. Serta adik-adik tercinta, OK.Denny Zulham, SE, Ir.Ida Zulfida, MS, Ir.OK.Hery Zulfan, OK.Ahmad Fauzi, SE, MM dan Sofyan Hidayat, SE (Ak), M.Ec, adalah semua keluarga besar yang tak pernah putus dalam do’anya dalam perjalanan hidup kami, kami sekeluarga berhutang budi pada semuanya dan capaian hari ini adalah capaian kita semua. Keluarga “Opung Siantar”, Bachtiar Sinaga, Dedy dan Agnes adalah juga keluarga yang senantiasa berdo’a buat keberhasilan kami. 38 Ibu susu kami Alm Atika dan Uwak kami Abdullah Sani dan keluarga adalah sosok yang terus melimpahkan kasih sayangnya kepada kami hingga akhir hayatnya, semoga Allah senantiasa melimpahkan Rahman dan Rahimnya. Khusus kepada shohib kami dalam masa-masa awal perjuangan hingga hari ini duduk sebagai Gubernur Simatera Utara, Ir.Gatot Pudjo Nugroho,M.M. adalah juga sosok yang patut kami beri aprisiasi, karena betapapun juga cita-cita Keadilan yang pernah kita impikan dahulu, mestilah terus terpatri dalam jiwa kita untuk secara terus menerus kita perjuangkan. Abangda Nurdin Lubis, SH,MM adalah sosok yang yang pantas mendapat apresiasi dari kami karena bagaimnapun juga abang telah mengajarkan kami bagaimana cara berorganisasi dengan baik. Karena itu kesempatan yang berbahagia ini kami gunakan untuk mengucapkan rasa terima kasih kami yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya kepada kita semua, Aamin ya Rabbil Alamin. Secara khusus buat sahabat dalam suka dan duka dalam mengharungi pendidikan sejak masa S2 beberapa tahun yang lalu dan kebersamaan itu terulang lagi pada jenjang S3, hari-hari duka ketika harus menyiapkan tugas-tugas kuliah sampai pada hari-hari penuh suka ria ketika studi di beberapa perpustakaan di Eropa. Shohib tercinta, Dr.Tarmizi, SH.M.Hum dan Dr.Abdul Hakim Siagian, SH, M.Hum adalah sahabat-sahabat setia dan memiliki andil besar dalam penyelesaian studi ini. Terima kasih untuk semuanya. Kepada Isteriku Hj.Syarifah Sufina, SH yang kehilangan banyak waktu kecuali untuk mengurus kami, betapapun juga tiap buah pikiran yang terurai dalam disertasi ini adalah buah amal dan keikhlasannya yang tanpa pamrih, terima kasih isteriku. Untuk anak-anak ku yang baik budi, OK.Saddam Shauqi, SH, OK.Ahmad Yasser Tohari, SH, OK.Akbar Tofani, dan OK. Mohd. Sofi Fauzan, ma’afkan abah telah mengambil waktu gembira dan senda gurau yang semestinya dapat kita lalui bersama, akan tetapi sebahagian waktu itu telah terpakai oleh pekerjaan yang amat mulia ini. Kalian semua telah kehilangan banyak hak dan kenikmatan dari abah, antara lain kehilangan untuk menikmati racikan hidangan panas dari abah untuk kita nikmati pada acara makan malam bersama. Sekali lagi ma’afkan abah, tanpa dukungan dan kerelaan kalian semua mungkin abah tidak pernah berdiri di sini pada forum yang sangat mulia ini. Kesemua itu hari ini telah tertebus, karena itu hari ini semua capaian ilmiah yang abah peroleh ini akan abah dedikasikan untuk kalian, untuk semua keluarga, sahabat, para guru 39 yang tak satupun tersisa dalam menyemangati kami hingga studi ini dapat selesai dengan baik. Lembaran kertas ini ternyata tak cukup mampu untuk menampung rasa syukur dan ingin rasanya menyampaikan terima kasih kepada siapapun tempat kami berhutang bndi, tapi keterbatasan jualah membuat ucapan ini harus kami akhiri. Bagi mereka yang tak sempat disebut namanya dalam perhelatan ini, adalah juga mereka yang berjasa pada kami, untuk itu mohon ma’af atas kealpaan kami dan semoga Allah tetap melimpahkan RahmatNya pada kita semua. Akativitas penulisan sebuah studi ilmiah, sekalipun menggunakan kerangka teori ilmiah, tunduk pada aturan metodologi ilmiah, akan tetapi dalam analisis dan penggunaan bahasa tetaplah tunduk pada faktor-faktor subyektif peneliti. Oleh karena itu pekerjaan penelitian pada babak-bababak terakhir penyusunan laporan penelitian adalah pekerjaan seni dengan mengandalkan talenta, seperti pekerjaan melukis di atas kanvas tanpa menggunakan penghapus, sehingga kerap kali ditemui nilai nilai subyektifitas dan kemungkinan menjadi kurang obyektif, tidak ilmiah dan itu tentu sangat mengganggu para pembaca. Akan tetapi di sisi lain sebagai hasil kerja ilmiah dan berujung pada hasil kerja seni yakni seni menulis, tentu saja ada bahagian-bahagaian tulisan ini yang perlu mendapat renungan guna pencerahan hukum di negeri ini. Faktor subyektif dalam tulisan ini pasti tak dapat dihindarkan, begitupun semua itu tetaplah menjadi tanggung jawab kami dan kepada pembaca terus kami harapkan kritik dan saran demi penyempurnaannya, tentu saja dengan begitu faktor subyektif yang ada dalam studi ini sedikit demi sedikit dapat dikurangi, hingga berakhir menjadi sebuah karya yang bernilai akademis tinggi. Naskah ini mungkin tidak dapat tersusun seperti apa yang terhidang hari ini, tanpa keterlibatan Basaria Tinambunan,SH dan Juliana yang dengan teliti mengetik huruf demi huruf. Kesetiaan kalian berdua yang hampir dua dasawarsa menghabiskan waktu bersama kami dan menyaksikan anak-anak kami tumbuh adalah budi baik yang tidak bisa kami sekeluarga membalasnya. Abang dan Kakak berhutang budi pada kalian berdua, dan abang yakin kebaikan kalian tidak akan sia-sia dan Tuhan akan terus mengalirkan kebaikan dalam kehidupan kalian di masa-masa yang akan datang. 40 Akhirul kalam Billahittaufiq wal hidayah Wassalamu’alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh. Medan, 3 Maret 2016 Dr. OK. Saidin, SH, M.Hum 41 DAFTAR ISI PENGANTAR PROF. HIKMAHANTO JUWANA, SH., LL.M., Ph.D .......................................................................... ii KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH ............ v DAFTAR ISI .......................................................................... xxii DAFTAR MATRIK ....................................................................... xx DAFTAR SKEMA .......................................................................... xxiv DAFTAR GRAFIK ......................................................................... xxv DAFTAR TABEL .......................................................................... xxvi DAFTAR SINGKATAN ................................................................. xxvii PROLOG .......................................................................... 1 BAB I : PENDAHULUAN ............................................ 19 A. Latar Belakang ......................................... 19 B. Teori, Konsep dan Metode ...................... 42 B.1. Teori ................................................ 42 B.2. Konsep ............................................ 59 B.3. Metode............................................. 61 CHAPTER II : THE DYNAMICS OF THE HISTORY OF LEGAL POLICY IN THE TRANSPLANT OF COPYRIGHT LAW ................................... 79 A. Introduction................................................ 79 B. Auteurswet Period Stb No. 600 (19121982) ......................................................... 83 C. Period of Copyright Law number 6 of 1982 (1982 - 1987).................................... 92 D. The Period of Copyright Law Number 7 of 1987 (1987 - 1997)................................ 110 E. The Period of Copyright Law Number 12 of 1997 (1997 - 2002)................................ 136 F. Period of Copyright Law Number 19 of 2002 (2002 - 2014).................................... 161 G. The Period of Copyright Law Number 28 of 2014 (2014 - now)................................. 181 H. Analysis and Invention .............................. 186 BAB III : POLITIK HUKUM : PERGESERAN NILAI FILOSOFIS ...................................................... 178 A. Pengantar ................................................... 178 B. Perubahan dan Pergeseran Nilai Ketuhanan ............................................... 188 C. Perubahan dan Pergeseran Nilai 42 Kemanusian ............................................. D. Perubahan dan Pergeseran Nilai Kebangsaan ............................................... E. Perubahan dan Pergeseran Nilai Musyawarah dan Mufakat ......................... F. Perubahan dan Pergeseran Nilai Ekonomi Pancasila .................................. G. Analisis dan Temuan ................................... BAB IV : PILIHAN POLITIK HUKUM UU HAK CIPTA NASIONAL ......................................... A. Pengantar ................................................... B. Substansi Hukum ...................................... 1. Paradigma Filosofis ..................... 2. Paradigma Juridis .................... 3. Paradigma Politis .......................... C. Struktur Hukum ........................................ 1. Lembaga Pembuat UU (Legislatif) . 2. Lembaga Penegak Hukum (Yudikatif) 3. Lembaga Pemerintah (Eksekutif) ..... D. Budaya Penegakan Hukum .................... 1. Budaya Hukum Legislatif .................. 2. Budaya Hukum Eksekutif .................. 3. Budaya Hukum Judikatif: .................. 4. Budaya Hukum Masyarakat ................ E. Penegakan Hukum Hak Cipta Dalam Bidang Sinematografi .............................. F. Gagasan Ideal Pilihan Politik Hukum Ke Depan ........................................................ 1. Think Globally ..................................... 2. Commit Nationally ............................... 3. Act Locally ........................................... G. Analisis dan Temuan .............................. EPILOG .......................... DAFTAR PUSTAKA .......................... INDEKS RIWAYAT SINGKAT PENULIS 198 210 224 240 250 256 256 258 259 271 278 286 292 303 311 321 322 330 344 358 368 385 401 407 413 429 441 447 43 DAFTAR MATRIK Matrix 1 Matrix 2 Matrix 3 Matrix 4 Matrix 5 : : : : : Auteurswet 1912 Stb. No. 600 Norms Transplant Into Act No. 6 of 1982 (Norms Regarding Copyright Terminology) ........................................ 93 Auteurswet 1912 Stb. No. 600 Norms Transplant Into Act No. 6 of 1982 (Norms Regarding Author Terminology) ......................................................... 94 Auteurswet 1912 Stb. No. 600 Norms Transplant Into Act No. 6 of 1982 (Norms Regarding Protected Creation) ................................................ 95 Auteurswet 1912 Stb. No. 600 Norms Transplant Into Act No. 6 of 1982 (Norms Regarding The Time Period of Copyright) ..................................... 97 Auteurswet 1912 Stb. No. 600 Norms Transplant Into Act No. 6 of 1982 (Norms Regarding Copyright Limitation) ......................................................................... 98 Matrix 6 : Auteurswet 1912 Stb. No. 600 Norms Transplant Into Act No. 6 of 1982 (Norms Regarding NonCopyrighted Creation)............................................ 100 Matrix 7 : Auteurswet 1912 Stb. No. 600 Norms Transplant Into Act No. 6 of 1982 (Norms Regarding The Prohibition of Copyright Use) ............................... 101 Matrix 8 : Auteurswet 1912 Stb. No. 600 Norms Transplant Into Act No. 6 of 1982 (Norms Regarding Moral Right) ...................................................................... 102 Matrix 9 : Auteurswet 1912 Stb. No. 600 Norms Transplant Into Act No. 6 of 1982 (Norms Regarding Registration System of Copyright) ........................... 102 44 Matrix 10 : Matrix 11 : Auteurswet 1912 Stb. No. 600 Norms Transplant Into Act No. 6 of 1982 (Norms regarding Criminal Charges) 103 Auteurswet 1912 Stb. No. 600 Norms Transplant Into Act No. 6 of 1982 (Norms Regarding Civil charges)...... 104 Matrix 12 : Alteration from the Act number 6 of 1982 to the Act number 7 of In Criminal Aspect ...................... 123 Matrix 13 : Alteration of the Act Number 6 of 1982 to The Act Number 7 of 1987 Based on Criminal Classification...... 125 Alteration Act Number 6 of 1982 to The Act Number 7 of 1987 Based on The Scope of Enforcement ................. 126 The Alteration of Act Number 6 of 1982 to The Act Number 7 of 1987 Based on Time Period........................ 127 The Alteration of Act Number 6 of 1982 to The Act Number 7 of 1987 Based on the Relationship Between Country and Copyright Holder ......................................... 131 Matrix 14 : Matrix 15 : Matrix 16 : Matrix 17 : The Regulation Basis of the Publishing of Act Number 6 of 1982 And the Act Number 7 of 1987 135 Matrix 18 : Transplantation of TRIPs Agreement Into The Act Number 12 of 1997 Regarding Rental Rights ................. 144 Transplantation of TRIPSs Agreement Into The Act Number 12 of 1997 Regarding Neighbouring Rights ..... 145 Matrix 19 : Matrix 20 : Transplantation of TRIPS Agreement into the Act number 12 of 1997 Regarding Copyright License . 150 Matrix 21 : Alteration of Act Number 7 of 1987 to The Act Number 12 of 1997 Based on Protection Aspect on Unknown Creator or a Creation ....................... 152 Matrix 22 : Alteration of Act number 7 of 1987 to The Act Number 12 of 1997 Based on The Exception of Copyright Violation .............................................. 154 45 Matrix 23 : Alteration of Act Number 7 of 1987 to The Act Number 12 of 1997 Regarding the Time Period of The Work’s Protection ........................................................................... 155 Matrix 24 : Alteration of Act Number 7 of 1987 to Act Number 12 of 1997 Regarding The Right and Authority to Accuse .............................................. 157 Matrix 25 : Alteration of Act number 7 of 1987 to The Act Number 12 of 1997 Regarding Civil Servants Investigator ............................................................ 159 Matrix 26 : Alteration of Act number 12 of 1997 to Act number 19 of 2002 Regarding the Criminal Aspect ................................................................... 165 Matrix 27 : Transplantation of TRIPs Agreement Into The Act Number 19 of 2002. .......................................................... 168 Basis of Legislation in Enacting the Act Number 12 of 1997 and Act Number 19 of 2002 ................................... 174 Matrix 28 : Matrik 29 : Pentingnya Agama Dalam Kehidupan ................... 194 Matrik 30 : Kewenangan Eksekutif Untuk Membuat Peraturan Pelaksana Undang-undang No. 19 Tahun 2002 ............................................................ 203 Matrik 31 : Perencanaan Pembangunan Era 1945-2025 ........... 279 Matrik 32 : Kinerja Lembaga Pembuat Undang-undang (1945 – 2012) ................................................................... 283 Matrik 33 : Gugatan Uji Materil Terhadap Undangundang di Mahkamah Konstitusi......................... 284 Matrik 34 : Tipologi Putusan Gugatan Uji Materil Terhadap Undang-Undang Kurun Waktu 2011 ..................... 284 Matrik 35 : Kebijakan Pembangunan Hukum Hak Cipta Dalam Kurun Waktu Kepemimpinan Presiden ..... 316 46 Matrik 36 : Matrik Pelanggaran Hukum Yang Dilakukan oleh Anggota Legislatif DPR-RI.................................... 324 Matrik 37 : Paradigma Hukum.................................................. 337 Matrik 38 : Pejabat Eksekutif Terlibat Kasus Pelanggaran Hukum dan Moral .................................................. 340 Matrik 39 : Pelanggaran Hukum Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum ..................................................... 346 Matrik 40 : Film Produksi Tahun 1926-1932............................ 372 Matrik 41 : Film Produksi 1933-1936....................................... 373 Matrik 42 : Film Produksi Tahun 1937-1942............................ 373 Matrik 43 : Film Produksi Tahun 1942-1944............................ 375 Matrik 44 : Data Statistik Produksi Film Indonesia 2002 – 2012 ....................................................................... 377 47 DAFTAR SKEMA Skema 1 Resultan Kekuatan Tarik Menarik Dalam Politik Hukum.................................................................... 34 : Law Enforcement Hak Cipta .................................. 36 Skema 3 : SISPOLINDO (Sistem Politik Indonesia) Menurut Analisa Kesisteman ................................................ 51 Sisbangkumnas (Sistem Pembangunan Hukum Nasional) ................................................................ 53 Kerjasama Teoritisi dan Praktisi Dalam Upaya Pembinaan Hukum ................................................. 55 Skema 2 : Skema 4 : Skema 5 : Skema 6 : Teori Nuances Mahadi ........................................... 57 Skema 7 : Bagan Alur Kerangka Teori dan Kerangka Konsep ................................................................... 58 Skema 8 : Perkembangan Sistematika Hak Cipta Dalam Sistem Hukum Perdata ........................................... 234 Skema 9 : Kedudukan Hak Cipta Dalam Sistem Hukum Perdata.................................................................... 236 Skema 10 : Siklus Politik Unifikasi Hukum Dalam Negara Hindia Belanda....................................................... 266 Skema 11 : Siklus Ideologi Pembentukan Undang-undang Hak Cipta ............................................................... 268 48 Skema 12 : Tempat Karya Sinematografi Dalam Sistem Hak Kebendaan.............................................................. 276 Skema 13 : Transplantasi Hukum Perdata Eropa ...................... 390 DAFTAR GRAFIK Grafik 1 : Ketimpangan Ekonomi di Berbagai Dunia ............ 247 Grafik : 2 : Karya Sinematografi Bajakan Yang Diperdagangkan di Gerai Tradisional di Kota Medan .................................................................... 364 Grafik : 3 : Karya Sinematografi Bajakan Yang Paling Banyak Terjual di Gerai Tradisional di Kota Medan .................................................................... 366 Grafik : 4 : Produksi Film Dunia Tahun 2012 .......................... 381 49 DAFTAR TABEL Tabel 1 : Tingkat Pengetahuan Aparat Kepolisian Terhadap Peristiwa Pidana Pembajakan Hak Cipta Karya Sinematografi ......................................................... 355 Tabel 2 : Langkah Tindakan yang Diambil oleh Pihak Kepolisian Atas Pembajakan Hak Cipta Karya Sinematografi ......................................................... 355 Tabel 3 : Legalitas Barang-barang yang Dijual ..................... 356 Tabel 4 : Kecenderungan Konsumen Membeli VCD dan DVD Hasil Bajakan .............................................. 358 Tabel 5 : Pilihan Konsumen Untuk Membeli Barang Legal dan Illegal .............................................................. 359 Tabel 6 : Tingkat Pengetahuan Konsumen Terhadap Aspek Hukum Pembajakan Karya Sinematografi ............. 360 Tabel 7 : Tindakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Aparat Terhadap Konsumen yang Membeli Produk VCD dan DVD Illegal .................................................... 360 Tabel 8 : Peringkat Industri Film Amerika Dalam Memberikan Sumbangan Pendapatan Domestik Dibandingkan dengan Industri Yang Lain ........... 382 Tabel 9 : Domestic filmed entertainment revenues, 1986 and 1991 ................................................................. 383 50 DAFTAR SINGKATAN ADB ASEAN ASI REVI BLBI BPHN BUMN BW DBR GN DVD GATT GBHN G-8 G-20 HKI IMF IKAPI Ipoleksosbud IS IPTN KPK KUHAP KUHD KUHPidana KUHPerdata LPHN MA MK MPA MPR NKRI OPI POLRI : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Asian Development Bank Association of South East Asia Nations Asosiasi Video Rekaman Indonesia Badan Likuidasi Bank Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional Badan Usaha Milik Negara Burgerlijk Wetboek Disc Blue Ray Guide Number Digital Video Disk General Agreement on Tariffs and Trade Garis-garis Besar Haluan Negara Group of Eight Group of Twenty Hak Kekayaan Intelektual International Monettary Fund Ikatan Penerbit Indonesia Ideologi politik, ekonomi, sosial dan budaya Indische Staatsregeling Industri Pesawat Terbang Nusantara Komisi Pemberantasan Korupsi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Kitab Undang-undang Hukum Dagang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kitab Undang-undang Hukum Perdata Lembaga Pembinaan Hukum Nasional Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Motion Pictures Association Majelis Permusyawaratan Rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia Operation Performance Improvement Kepolisian Republik Indonesia 51 Polresta Polsek PPNS Prolegnas PTBI QS Relegnas RPJPN Sisnas Sispolindo SP3 Stb TAP Tipikor TRIMs TRIPs TUN UNESCO UUHC VCD WCT WIPO WTO WPPT : : : : : : : : Kepolisian Resort Kota Kepolisian Sektor Penyidik Pegawai Negeri Sipil Program Legislasi Nasional Persatuan Toko Buku Indonesia Qur’an Surat Rencana Legislasi Nasional Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional : Sistem Nasional : Sistem Politik Indonesia : Surat Perintah Penghentian Penyidikan : Staatblad : Tunis Afrique Presse : Tindak Pidana Korupsi : The Agreement on Trade-Related Investment Measures : Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights : Tata Usaha Negara : United Nation Educational Scientific and Cultural Organization : Undang-undang Hak Cipta : Video Compact Disk : World Copyrights Treaty : World Intellectual Property Organization : World Trade Organization : WIPO Performances and Phonogram Treaty 52 PROLOG Sama dengan kajian bidang ilmu lainnya, kajian (ilmu) bidang hukum juga mempunyai sejarahnya sendiri. Tempat sejarah hukum dalam sistematika ilmu pengetahuan ditempatkan dalam lapangan humaniora, bidang kajian (ilmu) sejarah. Kajian sejarah hukum adalah sebuah kajian terhadap hukum dengan pendekatan (ilmu, metodologi, metode, teori) sejarah. Seperti apa hukum masa lampau, bagaimana cara mengetahui hukum yang berlaku pada priode tertentu, bagaimana bentuk hukum dan penegakannya pada berbagai preodik, bagaimana perubahan hukum dari satu masa ke masa berikutnya, apakah ada kausalitas anatara pemberlakuan hukum pada masa lalu dengan pilihan (politik) hukum pada masa berikutnya. Begitu juga dengan pertanyaan apakah pada abad modern secara simetris hukum berjalan seiring dengan lahirnya hukum modern pula. Itu adalah sebahagian saja dari pertanyaan-pertanyaan yang memiliki keterkaitan dengan studi sejarah. Dalam konteks hukum Indonesia, keberadaan hukum Indonesia hari ini tidak terlepas dari dinamika perjalanan sejarah politik hukum sejak jaman Hindia Belanda (dan bahkan sebelumnya) hingga pasca kemerdekaan. 19 Upaya untuk membangun tatanan (sistem) hukum Indonesia adalah sebuah upaya politik yang memang secara sadar dilaksanakan yakni dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang berakar pada transformasi kultural budaya Indonesia asli dan dikombinasikan dengan budaya (hukum) asing yang berasal dari luar dengan segala keberhasilan dan kegagalannya. Transformasi kultural ini di dalamnya menyiratkan transplantasi hukum (yang juga adalah merupakan bahagian dari sub sistem politik dan sub sistem budaya) yang berasal dari proses perjalanan sejarah peradaban Bangsa Indonesia. Pada hakekatnya tidak ada suatu produk hukum yang lahir di Indonesia tidak bersumber dari proses transformasi kultural yang berpangkal pada budaya yang beraneka ragam dan transplantasi budaya asing dalam proses yang disebut sebagai akulturasi dan inkulturasi dalam ruang sosial pada kurun waktu yang panjang. Dalam konteks ini, studi sejarah hukum akan menjadi lebih kaya dengan pemanfaatan ilmu-ilmu sosial seperti ilmu politik, ilmu 19 Sebelum masuknya Pemerintah Kolonial Belanda tatanan masyarakat nusantara telah memiliki hukum asli berupa norma adat, norma agama dan norma kebiasaan yang oleh Van Bollenhoven disebutnya sebagai adat recht, lihat Ter Haar, Asas-asas dan Tatanan Hukum Adat, Mandar Maju, Bandung, 2011. 53 ekonomi, sosiologi dan antropologi. Sejarah hukum tidak dapat dilepaskan dari perjalanan terbentuknya peradaban suatu bangsa. Sejak awal perkembangan tata hukum Indonesia yang bersumber dari hukum kolonial, demikian Soetandyo Wignjosoebroto 20 mengungkapkan adalah perkembangan yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan liberalisme yang mencoba untuk membukakan peluang-peluang lebar pada dan untuk modal-modal swasta dari Eropa guna ditanamkan kedalam perusahaan-perusahaan besar di daerah jajahan21 (namun juga dengan maksud di lain pihak tetap juga melindungi kepentingan hak-hak masyarakat adat ataupun hak-hak pertanian tradisional masyarakat pribumi). Perlindungan itu diberikan dengan cara mengefektifkan berlakunya hukum untuk rakyat pribumi, dengan member ruang berlakunya hukum adat. Formula yang digunakan adalah pemerintah Hindia Belanda membagi 3 (tiga) golongan penduduk (di wilayah Hindia Belanda ketika itu) 22 Penduduk di wilayah jajahan Hindia Belanda ketika itu dikelompokkan atas 3 (tiga) golongan yaitu : 1. Golongan Eropa atau yang dipersamakan dengan Eropa 2. Golongan Timur Asing (Timur Asing Tionghoa dan Timur Asing lainnya seperti Arap dan India). 3. Golongan Bumi Putera (penduduk Indonesia asli). Terhadap ketiga golongan penduduk ini diberlakukan hukum yang berbeda-beda. Untuk golongan Eropa atau yang dipersamakan dengan Eropa misalnya diberlakukan hukum Eropa yakni hukum Belanda yang berakar pada tradisi hukum Indo-Jerman dan RomawiKristiani yang dimutahirkan lewat berbagai revolusi yang kemudian dalam lapangan hukum perdata dimuat dalam Burgerlijk Wetboek (BW) dan Wetboek van Koophandel (WvK) atau yang dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Sedangkan untuk golongan Timur Asing Tionghoa sebahagian dinyatakan berlaku hukum perdata Belanda tersebut kecuali mengenai adopsi dan kongsi. Terakhir terhadap golongan Bumi Putera diberlakukan hukum adat, kebiasaan 20 Soetandyo Wignjosoebroto, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 1994, hal. 3. 21 Sebagai contoh adalah pembukaan besar-besaran lahan perkebunan tembakau, kelapa sawit, karet dan teh di wilayah Sumatera Timur. 22 Melalui Pasal 75 RR Lama dan kemudian diubah dengan 75 RR Baru yang sebelumnya juga telah dimuat dalam Pasal 6-10 AB dan terakhir dengan Pasal 131 dan 163 IS. Lihat lebih lanjut E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Ichtiar Baru, Jakarta, 1983, hal. 167. 54 dan hukum agamanya atau yang dikenal dengan Godien Stigwetten, Volkinstelingen en Gubreiken. Ada upaya pemerintah Hindia Belanda untuk mensejajarkan berlakunya hukum di negaranya dengan hukum yang berlaku di daerah jajahannya. Kebijakan ini kemudian dikenal dengan penerapan azas konkordansi. Meskipun kemudian kebijakan penerapan azas konkordansi ini mendapat perlawanan dari ilmuwan hukum Bangsa Belanda sendiri seperti Van Vollenhoven dan Ter Haar. 23 Dalam bidang hukum perdata, hukum dagang, dan hukum pidana serta hukum acara pidana dan perdata begitu juga hukumhukum lain yang tersebar secara sporadis ada upaya untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi hukum Eropa di tanah jajahan dan dijalankan dengan memberlakukan hukum yang berasal dari dalam negerinya. Pemberlakuan hukum Kolonial dengan asas konkordansi ini dikemudian hari menciptakan keadaan pluralisme hukum yang sebelumnya juga telah dipicu oleh perbedaan struktur dan kultur masyarakat Indonesia yang memang dilatar belakangi oleh suasana pluralisme. Dapat dikatakan bahwa dampak dari dinamika pilihan politik hukum Pemerintah Hindia Belanda tersebut sampai hari ini membuahkan hasil pluralisme hukum yang tidak berkesudahan. Ditambah lagi pasca kemerdekaan pemerintah Indonesia sendiri melakukan pilihan politik hukum yang tersendiri pula untuk memenuhi tuntutan tatanan hukum Indonesia pasca kemerdekaan. Tampaknya faktor politik tidak pernah lepas dari rangkaian kegiatan penyusunan tata hukum di Indonesia dari waktu ke waktu. 23 Lihat lebih lanjut, Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, ELSAM, Jakarta, 2002, hal. 266. Kisah ini diawali dari para pejabat Eropa yang direkrut untuk mengisi jabatan dalam pemerintahan kolonial dan untuk itu perlu pendidikan secara khusus di berbagai kota di Belanda yaitu di Leiden, Delf dan Utrecht yang sebahagian besar diajarkan mengenai hukum, bahasa, adat, kebiasaan dan lembaga-lembaga agama rakyat pribumi di daerah koloni. Di ketiga kota yang beroperasi lembaga pendidikan itu Leiden tercatat paling besar dan paling banyak berpengaruh karena Rijks Univesiteit yang berkedudukan di Leiden menjadi pusat pemikiran liberal yang menganut garis politik etis dalam menangani urusan koloni. Akan tetapi secara mengejutkan Leiden ternyata tidak bisa sejalan dengan rencana orang-orang resmi pemerintahan untuk menjalankan politik hukum pemerintah Hindia Belanda dan diantara orang-orang yang menggagalkan upaya itu adalah Van Vollen Hoven dan Ter Haar dikemudian hari lewat kedua orang inilah akhirnya orang-orang pribumi di Indonesia memiliki hukumnya sendiri yang kemudian dikenal dengan Adat Rechts atau hukum adat yang untuk pertama kalinya dipergunakan oleh Snouck Hurgronje dalam bukunya De Atjech hers dan Het Gajo Land. 55 Dalam konteks global, pengaruh tekanan politik asing (luar negeri) terus menerpa kebijakan pembangunan hukum di Indonesia. Terutama pasca ratifikasi GATT/WTO 1994 sebagai instrument globalisasi ekonomi (namun tetap membawa dampak pada sistem sosial lainnya) yang mengharuskan Indonesia menyesuaikan beberapa peraturan perundang-undangannya khususnya dalam lapangan Hak Kekayaan Intelektual dengan TRIPS Convention yang merupakan instrument hukum hasil Putaran GATT/WTO 1994, lapangan hukum investasi, lapangan hukum lingkungan, lapangan hukum perbankan dan bidang-bidang hukum ekonomi lainnya serta lapangan hukum yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia. Dominasi politik asing dan kepentingan politik negara maju tidak dapat dilepaskan dari langkah-langkah kebijakan negara Indonesia dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia bahkan undang-undang dalam bidang politik dan keamanan. Faktor yang turut mempengaruhi pilihan kebijakan politik itu tidak lain dikarenakan lemahnya penguasaan kapital dalam negeri Indonesia, rendahnya tingkat kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya manusia Indonesia dan memburuknya sistem pengelolaan manajemen negara. Inilah yang menurut M. Solly Lubis 24 sebagai sebuah kelemahan yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia dengan ungkapan sebagai berikut : Mereka (negara maju, pen) memiliki dan menguasai keunggulan strategis dalam tiga hal, yakni keunggulan capital (funds and equipment) keunggulan teknologi canggih dan keunggulan manajemen yang cukup rapid an tersistem dengan apik. Kelemahan dan ketergantungan kita di tiga bidang itu, sekaligus membuktikan lemahnya kemandirian kita dan ketergantungan inilah yang menyebabkan kita tidak bisa mengelakkan intervensi dan berbagai dikte terbuka ataupun terselubung oleh negara-negara lain itu terhadap kita. Bahkan disana-sini terasa sebagai eksploitasi ekonomi, dominasi politis dan penetrasi kultur, tiga target mana adalah merupakan tiga target utama pada kaum kolonialis-imperalis dan kapitalis. 24 Lihat lebih lanjut M. Solly Lubis M. Solly Lubis, Serba-Serbi Politik & Hukum, PT. Sofmedia, Jakarta, 2011, hal. 97. Lihat juga Sritua Arief & Adi Sasono, Indonesia Ketergantungan dan Keterbelakangan, Mizan, Jakarta, 2013. 56 Dominasi kebijakan politik ekonomi asing di Indonesia sebenarnya tidak hanya dimulai pada saat ratifikasi konvensi-konvensi yang berkaitan dengan perdagangan internasional seperti GATT/WTO serta konvensi-konvensi internasional lainnya. Perebutan negara-negara yang hari ini sebagai penguasa ekonomi di dunia yang tergabung dalam negara industri maju seperti G-8 dan G-20 berawal dari perjalanan sejarah yang cukup panjang. Peristiwa yang melatar belakangi munculnya Perang Dunia ke-2 adalah tidak terlepas dari perebutan sumber-sumber ekonomi yang ada di berbagai belahan bumi. Ekspansi negara-negara Eropa ke Asia, sebut saja misalnya Inggris ekspansi ke India, Burma, Hongkong dan Malaysia, Prancis ekspansi ke Indocina (Laos, Kamboja dan Vietnam), Belanda ekspansi ke Indonesia bahkan Amerika dengan sekutunya Inggris, Prancis dan Belanda turut mengontrol aktivitas di kawasan Pasifik. Sampai hari ini, negara-negara maju tersebut termasuk Jepang meskipun kalah dalam Perang Asia Timur Raya melawan negara-negara sekutu (Amerika dan Eropa) dominasi dalam politik ekonomi semakin hari semakin menguat hingga hari ini. Catatan yang dikemukakan oleh Stephen E. Ambrose dan Douglas G. Brinkley, 25 memberikan pencerahan untuk sampai pada suatu kesimpulan bahwa kekuatan politik ekonomi di berbagai belahan Asia masih dan akan terus beraada di bawah bayang-bayang kekuatan Barat (Amerika dan Eropa Barat) : On the other side of the world the United States, in combination with the British, French and Dutch, still ruled the Pacific. American Control of Hawaii and the Philippines, Dutch control of the Netherlands East Indies (N.E.I., today’s Indonesia), French control of Indochina (today’s Laos, Cambodia (Democratic Kampuchea), and Vietnam), and British control of India, Burma, Hong Kong and Malaya gave the Western powers a dominant position in Asia. Japan, ruled by her military, was aggressive, determined to end white man’s rule in Asia, and thus a threat to the status quo. But Japan lacked crucial natural resources, most notably oil, and was tied down by her war in China. Pada hakekatnya uraian berikut ini akan mencoba untuk membawa pembaca ke alam studi sejarah hukum. Menelusuri ruang sosial tempat diberlakukannya hukum dalam berbagai penggalan waktu 25 D Stephen E. Ambrose and Douglas G. Brinkley, Rise to Globalism, American Foreign Policy Since 1938, Penguin Books, London, 2011, hal. 1. 57 Arti Penting Kajian Sejarah Hukum. Studi hukum melalui pendekatan sejarah akan dapat membantu untuk sampai pada satu harapan bahwa ke depan akan dapat dirumuskan hukum-hukum yang lebih bernuansa humanis dan berkeadilan dan menampung berbagai harapan dan cita-cita Negara. Studi sejarah hukum menjadi sangat penting manakala hukum masa lalu dan yang sedang berlaku hari ini belum mampu memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan. Perlunya kajian atau studi sejarah terhadap hukum paling tidak memiliki alasan ilmiah : Pertama : sangat sedikit studi-studi hukum yang dilakukan melalui pendekatan sejarah. Kedua : terjadi keterputusan sejarah yang disebabkan oleh ketiadaan jembatan-jembatan penghubung antara generasi sarjana hukum sebelum kemerdekaan, generasi pasca kemerdekaan periode kepemimpinan Bung Karno, generasi pasca kepemimpinan Bung Karno (periode kepemimpinan Soeharto dengan rezim orde barunya), generasi pasca kepemimpinan Soeharto yakni generasi orde reformasi dan generasi orde pasca reformasi sehingga studi-studi hukum yang dilakukan kering dari pembelajaran sejarah dan ini membawa dampak pada terbelenggunya peradaban hukum pada situasi yang pragmatis. Ketiga : Tidak dimasukkannya dalam kurikulum pendidikan hukum pada strata I tentang materi pengajaran sejarah hukum, padahal data sejarah hukum cukup banyak tersebar di berbagai arsip dan perpustakaan. Keempat : Harus ada yang melanjutkan jembatan yang berisikan narasi sejarah hukum untuk menyambungkan keterputusan sejarah guna dapat memaknai budaya hukum Indonesia yang tepat dalam rangka pilihanpilihan politik hukum guna pembangunan sistem hukum nasional di masa yang akan datang. Kelima : Tanpa disadari telah terjadi perang kepentingan atau interes antara mereka-mereka yang berfikir pragmatis, praktis, jalan pintas, melawan kepentingan yang memperlihatkan kesadaran hukum yang memberi makna bahwa jatuh bangunnya peradaban mestilah berakhir dengan kemenangan peradaban yang adil dan merujuk pada pilihan ideologi yang telah diletakkan 58 pada saat negara ini didirikan yang mengacu pada the original paradigmatic value of Indonesian culture and society jika kita tidak ingin sejarah hukum kita terputus sebab pembiasan yang dalam tradisi keilmuan dinamai proses internalisasi mengenai yang baik, yang benar, yang indah, yang adil, yang beradab, serta suci bersumber dari kehidupan para tokoh-tokoh yang dapat dijadikan teladan. Beribu-ribu ajaran kognisi pengetahuan dan hafalan tentang teks-teks normatif akan percuma saja apabila sosok yang berjasa dalam meletakkan dasar-dasar pembangunan hukum dalam sejarah kita, yaitu para pendiri bangsa, guru-guru bangsa, mereka-mereka yang secara terus mempertahankan hukum adat dan berbagai pengorbanan demi pengorbanan yang mereka lakukan untuk meletakkan dasar pembangunan hukum bangsa ini. Dan tokoh-tokoh semacam itu saat ini sudah sulit untuk kita temukan. Jika tulisan ini memilih teori yang dikembangkan oleh para akademisi yang dalam karier dan kehidupannya telah menghabiskan masa untuk pembangunan hukum dan pembangunan ilmu hukum seperti, Mahadi dan M. Solly Lubis, serta Hikmahato Juwana ini bukanlah semata-mata untuk memperkenalkan pemikiran-pemikiran mereka - yang satunya hendak membangun hukum Indonesia modern, yang satunya lagi hendak meletakkan dasar pembangunan hukum Indonesia melalui hukum adat sebagai dasar dan terakhir kesemuanya hendaklah diletakkan dalam satu kerangka sistem yang disebut sebagai sistem hukum nasional - akan tetapi lebih jauh menggiring generasi yang akan datang untuk dapat memahami sejarah perjalanan hukum Indonesia, dan di negeri ini ternyata banyak pandangan dan pemikiran yang lahir dari anak bangsa sendiri, yang faham tentang kebutuhan hukum di negerinya, sebab membangun hukum bukanlah semata-mata melakukan sesuatu akan tetapi mempelajari sesuatu. Dengan lima alasan tersebut di atas, anak bangsa di negeri ini harus punya kemauan dan dengan rendah hati mengakui keterputusan sejarah peradaban hukum - karena kita harus menyadari pula bahwa ingatan kita sangat pendek - dan ketidak pedulian kita sendiri terhadap 59 pilihan-pilihan politik dalam pembangunan hukum nasional. Kini, mari kita rajut kembali benang-benang sejarah yang putus dan mempelajari kembali “situs-situs” yang saat ini memerlukan guru-guru yang dapat memikirkan dan menterjemahkan serta menafsirkan situs-situs itu. Saat ini diperlukan sosok intelektual hukum yang memahami sejarah karena kita tidak ingin terjadi apa yang pernah dikatakan oleh Sartono Kartodirdjo, “jangan menjadi cendekiawan model pohon pisang yang sekali berbuah lalu selesai”.26 Teruslah merajut benang-benang sejarah yang terputus agar untaian-untaian sejarah hukum Indonesia dapat dirajut dalam suatu “kain” yang bermakna lembaran sistem hukum nasional Indonesia. Salah satu kebijakan yang perlu ditempuh dalam pembangunan hukum adalah terciptanya suatu tatanan hukum yang dapat menjembatani kepentingan masyarakat Indonesia yang saling berbenturan sebagai akibat dari tawaran kultur yang plural. Perbedaan pada kultur dan berpengaruh pada budaya hukum ini berawal dari perjalanan sejarah yang cukup panjang yang memperlihatkan adanya pengaruh sistem hukum asing (yang sejak awal juga sudah ada perbedaan yakni antara sistem hukum Eropa Kontinental di satu pihak dan sistem hukum Anglo Saxon di pihak lain) terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (lokal) Indonesia (hukum adat). 27 Paling tidak dengan kebijakan itu perbedaan-perbedaan pada sistem hukum itu dapat sedikit demi sedikit (secara berangsur-angsur) dihapuskan untuk kemudian menuju pada satu tatanan hukum yang dapat berterima dalam kehidupan masyarakat Indonesia namun tetap pula mampu mengantisipasi gelombang globalisasi yang ditawarkan oleh masyarakat internasional. Dengan bahasa yang sederhana harapan dari pilihan terhadap kebijakan yang semacam ini adalah untuk mengukuhkan kembali hukum rakyat (hukum adat) sebagai hukum yang hidup agar kepentingan masyarakat tetap terpelihara dengan baik, namun tetap eksis dan mampu menangkap setiap perubahan yang ditawarkan oleh peradaban modern. Apa sebenarnya yang ditawarkan oleh sistem hukum Eropa kontinental yang dalam pilihan terhadap kebijakan pembangunan hukumnya didasarkan pada konsepsi hukum yang terkodifikasi dengan rapi, tidaklah terlalu buruk untuk terus dikembangkan dalam strategi pembangunan hukum di Indonesia, yang dalam banyak hal lebih 26 Lebih lanjut lihat Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993. 27 Lihat Soetandyo Wignjosoebroto, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Rajawali Press, Jakarta, 1994. 60 memberikan kepastian hukum. Namun begitu, apa yang sesungguhnya yang dikembangkan oleh negara-negara penganut sistem hukum Anglo Saxon (Amerika dan Inggris meskipun keduanya ada juga perbedaan), yang menggantungkan pola pilihan dalam penentuan apa yang menjadi hukum melalui putusan hakim, adalah juga sangat sesuai bagi Indonesia. Oleh karena konsepsi hukum Adat Indonesia yang sejak lama didasarkan pada putusan fungsionaris hukum adat (teori Beslissingen Leer yang dikembangkan oleh Ter Haar) 28 adalah sangat sejalan dengan konsepsi yang ditawarkan oleh sistem hukum Anglo Saxon. Oleh karena itu pula, memadukan antara kedua kutub yang berbeda itu untuk dipertemukan dalam rangka kebijakan pembangunan hukum Indonesia menurut hemat kami adalah suatu langkah yang arif guna memberi arti bagi hukum rakyat Indonesia sebagai hukum yang hidup. Caranya adalah, mengangkat kembali ”nilai-nilai hukum yang hidup” dalam masyarakat Indonesia, melalui langkah-langkah metodologis yang lazim dikenal dalam ilmu hukum dengan memadukannya melalui pendekatan sejarah, guna memutakhirkan data sejarah masa lampau untuk kepentingan hari ini dan masa depan. Tempat Sejarah Hukum dalam Sistematika Ilmu Pengetahuan Sama dengan induknya - kajian dalam ilmu sejarah generalisasi dalam kajian sejarah hukum bersifat terbatas. Artinya kalau kita berbicara tentang Hukum Perancis itu tak dapat digeneralisasi untuk Hukum Indonesia. Kalau kita berbicara tentang hukum Di Turkey pada masa dinasti Osmania itu tak dapat digeneralisasi untuk hukum Indonesia pada Masa Kerajaan Majapahit. Mengacu pada premis tersebut maka dapatlah difahami bahwa kajian sejarah hukum memiliki keterbatasan generalisasi . Oleh karena itu menurut Kuntowijoyo 29 keterbatasan generalisasi itu dapat diatasi dengan bantuan ilmu-ilmu sosial lainnya yang cenderung bergerak ke arah generalisasi, walaupun harus diakui bahwa semua ilmu memiliki keterbatasan dalam menggeneralisasi tiap-tiap obyek kajiannya. Kajian sejarah terhadap hukum oleh sebagaian kalangan ilmuwan hukum, ditempatkannya sebagai kajian hukum empiris. Ketika 28 Lebih lanjut lihat Ter Haar Bzn, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, (Terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto), Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, dan Jakob Sumarjo, Jakob Sumardjo, Mencari Sukma Indonesia Pendataan Kesadaran Keindonesiaan di Tengah Letupan Disintegrasi Sosial Kebangsaan, AK Group, Yogyakarta, 2003. 29 Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1994. 61 Gustav Redbruch 30 memperkenalkan tujuan hukum yang dikenal dengan sebutan Idea das Recht yaitu bertujuan untuk : mewujudkan keadilan dalam masyarakat, menciptakan kepastian hukum dan memberikan kemanfaatan, maka seiring dengan itu munculklah beberapa bentuk kajian hukum. Bagaimana hukum dapat mewujudkan keadilan dalam masyarakat kajiannya dilakukan melalui studi Filsafat Hukum, bagaimana hukum dapat menciptakan kepastian (berprilaku, kepastian hak, dan lain-lain) hukum kajiannnya dilakukan melalui ilmu hukum (jurisprudence) dan bagaimana hukum dapat memberikan kemanfaatan bagi masyakat, bidang kajiannya adalah studi hukum empirik meliputi Sosiologi Hukum, Politik Hukum, Psikologi Hukum dan Antropologi Hukum. Dalam beberapa literatur ada yang menempatkan kajian sejarah hukum dalam studi hukum empirik. Akan tetapi menurut hemat kami, kajian sejarah hukum sama halnya dengan kajian perbandingan hukum haruslah ditempatkan dalam studi tersendiri. Sebab keduanya tidak mempersoalkan hukum dari aspek tujuannnya yakni untuk memberikan kemanfaatan pada masyarakat seperti pandangan Jeremy Bentham. 31 Oleh karena itu hukum tak lagi dapat dibatasi dari 3 (tiga) perspektif saja tetapi sudah saatnya dikembangkan melalui 5 (lima) perspektif. Lima cara pandang, lima paradigma. Di samping 3 (tiga) paradigma yang telah diperkenalkan, dua paradigma lainnya (yang selama ini ditempatkan sebagai bahagian dari studi hukum empirik) yaitu : kajian sejarah hukum dan perbandingan hukum, haruslah dikeluarkan sebagai pendekatan tersendiri. Studi sejarah hukum tunduk pada preposisi-preposisi pendekatan ilmu sejarah dan studi perbandingan hukum sekalipun bersifat metodologi ia harus juga ditempatkan pada paradigma tersendiri. 32 Studi sejarah hukum, tidak lagi memandang hukum sebagai kumpulan ide atau gagasan untuk mewujudkan keadilan seperti dalam 30 Gustav Radbruch, Rechts-Philosophie, K.F. Koehler Verlag Stuttgart, Germany, 1956. 31 Jeremy Bentham, The Principles of Morals and Legislation, Oxford University Press, Oxford, 1823. 32 Lebih lanjut lihat Menski, Werner, Comparative Law in a Global Context The Legal Systems of Asia and Africa, Cambridge University Press, New York, 2009 ; Orucu, Esin, Critical Comparative Law : Considering Paradoxes for Legal System in Transition, Deventer, 1999, Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking, 1959 ; Orucu, Esin, The Enigma of Comparative Law, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston, 2004 ; Orucu, Esin, dan Elspeth Attwooll & Sean Coyle, Studies in Legal Systems : Mixed and Mixing, Kluwer Law International, London/Boston, 1996. 62 definisi hukum menurut paradighma filsafat hukum, atau hukum dirumuskan sebagai sekumpulan norma atau peraturan yang bertujhuan untuk menciptakan kepastian hukum menurut permaknaan ilmu hukum normatif (jurisprudence) ataupun hukum dimaknai sebagai satu instrumen (lembaga) yang bertujuan untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat menurut pandangan ilmu hukum empirik, tetapi hukum dimaknai sebagai gagasan atau ide, sekumpulan norma dan sebagai instrumen atau lembaga yang berada pada ruang sosial pada masa atau priode waktu tertentu dengan segala dinamikanya. Itulah rumusan hukum menurut paradigma sejarah hukum. Selanjutnya paradigma perbandingan hukum, akan melihat hukum dalam kacamata komperatif. Bagaimana sisi-sisi persamaan dan perbedaan sistem hukum (mulai dari sudut pandang filosofis, normatif dan empiris sampai pada sudut pandang sejarah hukum) yang satu dengan hukum yang lainnya. Sehingga studi perbandingan hukum akan mengkoperasi antar hukum di belahan Dunia Barat dengan Belahan Dunias Timur, Hukum dengan landasan ideologi Sosialais dengan Hukum dengan Ideologi Kapitalis. Hukum dengan Ideologi Islam dengan Hukum yang didasarkan pada Ideologi Skularisme, Hukum di negara maju dengan Hukum di negara berkembang, hukum di negara denokratis dengan hukum di negara diktator, hukum di negara republik dengan hukum di negara monarchi dan bahkan hukum pada masa kolonial dengan hukum pada masa kemerdekaan, dengan menggunakan metode komperasi. Berdasarakan uraian di atas dapatlah kami turunkan matrik paradigma dalam kajian hukum sebagai berikut : Paradigma Filosofis hukum ideologi Juridis/normati f Sosiologis/huk um empiris Historis Konsep Tujuan Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal Hukum sebagai kaidah/norma sebagai produk eksplisit dari sumber kekuasaan politik yang sah Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat Keadilan Hukum dimaknai sebagai Melihat dinamika Bidang Kajian Hukum filsafat Kepastian hukum Jurisprudence (ilmu hukum normatif) Kemanfaatan Sosiologi Antropologi Politi hukum Psikologi hukum Law and Society Law in Action Sejarah hukum 63 Metodologis/ comparative law gagasan atau ide, sekumpulan norma dan sebagai instrument atau lembaga yang berada pada ruang sosial pada masa atau periode waktu tertentu dengan segala dinamikanya Sekumpulan ide, norma yang lahir pada ruang sosial, sistem, struktur dan kultur, kurun waktu yang berbeda-beda yang menyebabkan perbedaan pada pemberian makna dan sikap serta prilaku hukum masyarakatnya hukum masa lalu untuk merumuskan hukum masa depan Untuk bahan pertimbangan dalam pilihan politik hukum guna merumuskan sistem hukum yang lebih baik Studi perbandingan hukum. Matrik di atas memperlihatkan bahwa : Sejarah hukum memiliki ranah kajiannya sendiri, sama halnya dengan perbadingan hukum dan 3 (tiga) kajian hukum lainnya yang sudah dikenal lama dalam kepustakaan (ilmu) hukum. Bagan berikut ini memperlihatkan 5 (lima) paradigma terhadap hukum. Sosiologi Hukum Antropologi hukum Politik hukum Psikologi hukum Law in Action Law in Society Filsafat Hukum Hukum Jurispruden Ilmu hukum normatif Perbandingan Hukum Sejarah Hukum 64 Jika suatu studi hukum menggunakan pendekatan sejarah, para peneliti akan memasuki ranah kajian yang sangat luas dan membuat siapa saja yang berminat untuk melihat hukum melalui perspektif sejarah tidak akan pernah kering dari ide dan gagasan untuk dituliskan. Kajian dapat dimulai dari teorinya sampai pada konsep dan metodhe - sumber (data) - sejarahnya. Sama halnya denga studi sejarah, maka sejarah hukum tidaklah semata-mata mengungkapkan fakta sejarah yang berkaitan dengan hukum dari waktu ke waktu, tetapi lebih dari itu adalah dengan melihat pada perjalanan sejarah hukum suatu bangsa pada priode tertentu dapat lah menjadi bahan pertimbangan guna refleksi atau pilihan (politik) hukum untuk masa yang akan datang untuk mencioptakan keadaan (hukum) yang lebih baik, lebih mampu menjawab tantangan masa datang. Satu hal yang perlu difahami dalam paradigma sejarah hukum adalah hukum diberlakukan pada ruang sosial (bukan ruang hampa) pada masa atau priode waktu tertentu. Sama halnya dengan perubahan dalam masyarakat, maka hukum yang berada pada ruang sosial itu akan bergerak (berevolusi) seiring dengan berjalannya waktu. Itu sebabnya hampir dapat dipastikan apa yang dilarang oleh hukum hari ini adalah apa yang dahulunya dibolehkan. 33 Contoh jika ganja hari ini tidak boleh disalahgunakan, maka batasan tentang frase “disalahgunakan” itu telah berubah. Ganja tak boleh “diisap” seperti rokok, yang dahulu sebelum keluar UU larangan penyalah gunaan narkotika hal semacam itu dibolehkan. Sekarang tidak saja diisap, tapi disimpan pun dilarang, padahal daun dan biji ganja itu baik juga untuk campuran bumbu masak (membuat daging menjadi cepat empuk dan masakan lainnya menjadi gurih). Sejarah hukum telah mencatat juga bagaimana perintah raja menjadi hukum dan raja selalu dianggap tak pernah bersalah. Memasuki perkembangan Hukum Tata Negara Modern hal itu saat ini tak pernah dijumpai lagi, sekalipun negeri itu menganut sistem monarchi absolut.Kekuasaan Raja atau Kaisar pada zaman dahulu berbeda dengan kekuasaan Raja atau Kaisar pada zaman sekarang. Raja di Inggeris, Arab Saudi, Monaco, Belgia dan Kaisar di Jepang pada masa lalu telah meninggalkan hukum yang mengekang hak-hak rakyat, apalagi menitahkan suatu perintah yang melanggar hak azasi manusia. Itulah sejarah hukum yang dari waktu ke waktu mengalami perubahan.Meminjam ajaran tentang sistem hukum yang ditawarkan 33 G.W. Paton, A Textbook of Jurisprudence, Yayasan Gadjah Mada, Yogyakarta, 1955. 65 oleh Friedman 34 maka yang menjadi obyek kajian sejarah hukum adalah materi hukum yang berlaku (substansi) dan lembaga-lembaga hukum (struktur) serta prilaku hukum masyarakatnya (kultur) pada ruang sosial (tempat) dan priode (waktu) tertentu. Model Kajian Sejarah Hukum Untuk melukiskan sebuah kajian sejarah terhadap (sistem) hukum dalam satu kurun waktu tertentu, uraian berikut ini akan meminjam model yang dikembangkan oleh Marc Bloch ketika menguraikan tentang Sistem Feodalisme di Eropa. Model yang diperkenalkannya adalah model yang bersifat sinkronis dan diakronis dalam kajian sejarah sosial.Dengan meminjam model yang diperkenalkan oleh Bloch, dapat dijelaskan bahwa dalam model yang sinkronis hukum digambarkan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari, substansi, struktur dan kultur.Pendekatan yang digunakan oleh Friedman menyiratkan pada model sinkronis yang melihat potret hukum dalam keadaan statis dalam keadaan waktu nol.Sebuah model sinkronis lebih mengutamakan “lukisan yang meluas” dalam ruang dengan tidak memikirkan terlalu banyak mengenai dimensi waktunya. Sebaliknya, model yang diakronis lebih mengutamakan memanjangnya lukisan yang berdimensi waktu dengan sedikit saja luasan ruangan. Model sinkronis digunakan oleh studi (ilmu) hukum, sedangkan model diakronis digunakan oleh kajian (ilmu) sejarah. Dengan sedikit memodifikasi Johan Galtung 35 untuk menggambarkan hubungan antara kajian (ilmu) hukum yang sinkronis dengan kajian (ilmu) sejarah yang diakronis dapat kami tampilkan gambar berikut ini : 34 Friedman, Lawrence M., The Legal System A Social Science Perspective, Russell Sage Foundation, New York, 1975 35 Johan Galtung, Studi Perdamaian Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban, Pustaka Eureka, Surabaya, 2003. 66 Sinkronis Ilmu hukum Diakronis sejarah Sumber : Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1994, hal 37). Kajian (ilmu) hukum normatif selama ini hanya melihat hukum melalui model sinkronis, dengan menawarkan sturuktur dan fungsinya disertai dengan gambaran tentang latar belakang mengapa hukum itu diperlukan (biasanya dimuat dalam konsiderans ketika peraturan itu dilahirkan). Model diakronis tidak saja menawarkan struktur dan fungsinya akan tetapi juga menawarkan sebuah model dinamis sehingga hukum dilihat dalam arus gerak pada peristiwa demi peristiwaatau kejadian yang kongkret. Itulah tujuan penulisan sejarah hukum.Penulisan sejarah hukum harus menggunakan model diakronis dengan meklihat pada bahan-bahan hukum dan aktualitasnya. Jadi, lebih dari sekedar model-model yang kemudian diterapkan dengan paksa pada lukisan sejarahnya. Oleh karena pertumbuhan sejarah hukum suatu bangsa mempunyai jalannya sendiri (memang tidak tertutup kemungkinan adanya kesamaan) maka untuk setiap masyarakat perlu adanya model hukum yang dikembangkan sendiri. Menarik untuk dijadikan bahan pisau analisis sejarah berkaitan dengan 67 ungkapan ini, yakni pandangan Chambliss dan Seidman yang menurut hemat kami menjadi sangat relevan untuk dikutip: Robert B. Seidman 36 dalam studinya melahirkan teori yang sangat terkenal tentang pengadopsian atau transplantasi hukum asing ini yakni “Theory The Law of Nontransferability of Law”. Kegagalan sebuah negeri di Afrika (bekas jajahan Inggeris) untuk menerapkan hukum Inggris di bekas negara jajahannya itu segera setelah Inggris meninggalkan Afrika, adalah suatu bukti bahwa transplantasi atau adopsi itu gagal. Tapi tidak jarang pula, transplantasi hukum asing itu memperlihatkan hasil yang baik, walau pada awalnya kurang dapat diterima oleh masyarakatnya. Di Turki dan di beberapa negara bekas koloni Inggeris, seperti Malaysia, Singapura, transplantasi hukum asing itu dipandang cukup berhasil. Dalam sejarah pengambilalihan hukum asing untuk dijadikan hukum di negeri sendiri, untuk kasus di Indonesia memperlihatkan sisi keberhasilan dan kegagalannya untuk bidang-bidang hukum pidana, sejarah mencatat KUH Pidana Indonesia hari ini dapat diberlakukan di wilayah Republik Indonesia secara unifikasi. Demikian juga hukum formilnya yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Akan tetapi, transformasi hukum perdata khususnya yang diatur dalam Buku II KUH Perdata yang mengatur tentang tanah yang kemudian diadopsi dan dimodifikasi kedalam UUPA ternyata mengalami kegagalan. Persoalan agrarian dari waktu ke waktu di Indonesia belum dapat diselesaikan dengan instrument hukum yang didasarkan pada hukum peninggalan Kolonial dengan kombinasi hukum adat. 36 Lihat Seidman, Ann, Robert B. Seidman, State and Law in The Development Process Problem-Solving and Institutional Change in the Third World, St. Martin’s Press, 1994, hal. 69. Lihat juga Seidman, Robert B., The State, Law and Development, St. Martin's Press, New York, 1978, hal. 125.Indonesia sendiri dalam sejarah pemberlakuan KUH Perdata yang berasal dari Kolonial Belanda juga gagal. KUH Perdata oleh Mahkamah Agung hanya diposisikan sebagai pedoman saja bagi hukum untuk memutus, tapi bukan sebagai hukum formal yang ketat untuk diikuti. Begitupun setelah Buku II KUH Perdata dicabut selalu dibukukan dalam UUPA No. 5 Tahun 1960 tentang Hukum Agraria, dengan mengambil sebagian besar norma hukum KUH Perdata. Lihatlah konsep hak milik (eigendom). Konsep HGU (erfacht), Hak Pakai, Hak Guna Bangunan yang diambil dari BW gagal diimplementasi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Tak ada HGU Asing Sacfindo, Lonsum yang tidak diperpanjang akibatnya hak-hak atas tanah itu tak pernah dapat didistribusikan ke rakyat. HGU sama maknanya dengan hak milik, terkuat, terpenuh dan hilang fungsi sosialnya. Rakyat kehilangan sumber pekerjaan, akhirnya menjadi TKW di negara asing. Demikian juga tentang Hukum Lingkungan, Hukum Perlindungan Konsumen, gagal diterapkan di Indonesia. 68 Bagan berikut ini memperlihatkan bagaimana pengaruh berbagai komponen dalam ruang sosial pada tataran basic policy dan enachment policy dalam pembentukan hukum di Indonesia. Meminjam model yang dikembangkan oleh Chambliss dan disesuaikan dengan kondisi hukum Indonesia bagan berikut ini dapat membantu untuk sekedar memberikan penjelasan. Scema Legal Policy Process (Basic Policy and Enactment Policy) Indonesian Law Arena of choice Legislatif (Parlement/ Legislative) Pressure Power Person Basic Policy Secondary Roles Primary Roles Feedback Feedback Yudikatif (Judiciary) Pressure Power Institusional Arena of choice Pressure Power Institusional - International Convention - the interests of developed countries - political parties Law enforcement (Enactment Policy) Pressure Power Person and social group/steakholders Arena of choice Feedback Pressure Power Person Person Pressure Power Institusional Source : OK. Saidin, 2013, Transplantasi Hukum Asing ke Dalam Undang-undang Hak Cipta Nasional dan Penerapannya Terhadap Perlindungan Karya Sinematografi (Studi Kasus Tentang Dinamika Politik Hukum dari Auteurswet 1912 ke TRIPs Agreement 1994), Disertasi, Pascasarjana USU, Medan, p.17, dimodifikasi. 69 Sejarah hukum suatu bangsa akan selalu membawa warna hukum sendiri bagi bangsa itu. Masuknya peradaban Hindu, kemudian Islam telah membawa perubahan besar meskipun secara evolusi dalam perubahan tata hukum Indonesia. Demikian pula masuknya Koloni Portugis, Belanda dan Jepang telah juga membawa perubahan baru pada sistem hukum Indonesia. Alam kemerdekaan dan diikuti dengan tranformasi peradaban global tak sedikit pula membawa perubahan pada pilihan politik pembentukan hukum nasional Indonesia. Dengan meminjam pandangan sejarawan terkemuka Jan Vansia, dapatlah disimpulkan bahwa model diakronis akan menunjukkan bagaimana evolusi dari sebuah bentuk hukum dan menghilang+kan rekaan waktu nol. Model diakronis inilah sesungguhnya yang akan membuahkan kematangan dalam mengambil keputusan untuk melengkapi studi-studi dengan model singkronis. Dalam kajian sejarah hukum, hukum bukanlah suatu gejala pada waktu nol yang tidak berubah, tetapi sesuatu yang mengalami transformasi sepanjang waktu. Oleh karena itu menjadi sah penafsiran sosiologis, penafsiran antropologis untuk menjelaskan fenomena perubahan yang hukum “statis” tak mampu memberikan jawaban. Lebih dari itu penafsiran historis akan jauh lebih penting karena ia akan berbicara dan mengungkapkan penggalan-penggalan peristiwa (kejadian) yang tak terputus, yang dapat diurut dan dirunut dari waktu ke waktu untuk sampai pada penggalan terakhir yang juga akan bergerak maju secara dinamis. Rangkaian kejadian yang susul menyusul tidak saja menjawab mengenai apa yang ada akan tetapi akan menjawab mengapa sesuatu itu ada dan bagaimana terjadinya. Hubungan kausal antara satu peristiwa hukum dengan peristiwa hukum lainnya, pilihan politik hukum dengan pertarungan kekuasaan politik di badan legislatif, prilaku hukum penguasa dan rakyat berupa perbuatan-perbuatan dengan kesengajaan adalah merupakan esensi dari penulisan sejarah hukum.Sejarah hukum bukanlah suatu susunan sinkronis dari peristiwa hukum atau korelasi antar variabel hukum yang merupakan urutan sebuah situasi, tetapi sejarah hukum adalah urutan dinamis atau dialektis dengan waktu yang jelas. 70 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Persoalan pertama yang akan diketengahkan dalam penelitian ini adalah persoalan dinamika politik hukum37 pembentukan Undangundang Hak Cipta Nasional, yang diwarnai dengan dominasi hukum asing. Transplantasi hukum telah menjadi pilihan dalam kebijakan pembangunan hukum di banyak negara di dunia. Khusus Indonesia, dalam dinamika sejarah proses pembentukan peraturan perundangundangannya, transplantasi hukum telah menjadi pilihan politik hukum negeri ini. Dinamika sejarah politik hukum kelahiran Undang-undang Hak Cipta Nasional Indonesia mengalami sejarah yang panjang. Mulai zaman kolonial diawali dari Auteurswet 1912 Stb No. 600 hingga zaman pasca kemerdekaan. Selama kurun waktu pasca kemerdekaan hingga hari ini, telah berlangsung 5 (lima) kali perubahan Undangundang Hak Cipta Nasional Indonesia. Perubahan-perubahan itu semuanya memiliki nuansa dan latar belakang sosio-politik tertentu pada zamannya. Pada zaman sebelum masuk Kolonial Asing, terminologi hak cipta38 tidak dikenal dalam perbendaharaan kata-kata dalam hukum asli 37 Hikmahanto Juwana, Politik Hukum Undang-undang Bidang Hukum Ekonomi di Indonesia, dalam Jurnal Hukum Vol. 01 No. 1 Tahun 2005, Sekolah Pascasarjana USU, hal. 28-47. Berbagai tujuan dan alasan dari dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan disebut sebagai politik hukum (legal policy). Mengacu pada pendapat Hikmahanto Juwana bahwa Undang-undang Hak Cipta yang pernah berlaku di Indonesia adalah undang-undang yang dibuat secara sengaja oleh institusi negara dengan tujuan dan alasan tertentu. Terdapat banyak alasan ketika Undang-undang Hak Cipta Indonesia dibuat yang semula berasal dari Auteurswet 1912 Stb. 600 harus diubah dengan Undang-undang No. 6 Tahun 1982, kemudian disempurnakan melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1987 kemudian dirubah lagi dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1997, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2002. 38 Mengenai terminologi hukum hak cipta, lihat D David Bainbridge, Intellectual Property, Pearson Education Limited, England, 2002, hal. 16. Hak cipta adalah bahagian dari Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Hak kekayaan intelektual terdiri dari hak cipta dan hak kekayaan perindustrian. Hak cipta terdiri dari hak cipta original dan hak yang berhubungan dengan hak cipta (neighboring rights). Hak kekayaan industri terdiri dari hak paten, hak merek, hak desain industri, perlindungan varietas baru tanaman dan perlindungan elektronika terpadu. Lihat juga Catherine Colston, Principles of Intellectual Property Law, Cavendish Publishing Limited, London, Sydney, 1999, hal. 23. Bandingkan juga Cornish & Llewelyn, Intellectual Property : Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, Thomson, Sweet & Maxwell, 2003, hal. 18. Lihat lebih lanjut Andrew Christie & Stephen Gare, 71 Indonesia. Entah itu dalam terminologi hukum adat maupun dalam terminologi hukum kebiasaan. 39 Terminologi hukum hak cipta diambil dari terminologi hukum asing auteursrechts dalam terminologi hukum Belanda atau copy rights Blackstone’s Statutes on Intellectual Property, Oxford University Press, New York, 2004, hal. 35. Lihat juga Deborah E. Bouchoux, Protecting Your Company’s Intellectual Property, Broadway, New York, 2001, hal.42. Lihat juga Christopher May, The Global Political Economy of Intellectual Property Rights, The new enclosures Second Edition, Routledge, London, 2010, hal. 41. Lihat juga Jill McKeough, Kathy Bowrey & Philip Griffith, Intellectual Property Commentary and Materials, Lawbook Co, Australia, 2002. Lihat juga Thomas A. Stewart, Intellectual Capital The New Wealth of Organizations, Broadway, New York, 1997, hal. 19. Lihat juga Kenny K.S. Wong and Alice, A Practical Approach To Intellectual Property Law In Hong Kong, Sweet & Maxwell Asia, Hongkong, 2002, hal. 56. Lihat juga Xue Hong & Zheng Chengsi, Chinese Intellectual Property Law in The 21 st Century, Sweet & Maxwell Asia, Hong Kong, 2002, hal. 38. Lihat juga Peter J. Groves, Source Book on Intellectual Property Law, Cavendish Publishing Limited, London, 1997, hal. 11. Lihat juga Peter Tobias Stoll, Jan Busche and Katrin Arend, WTO – Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden – Boston, 2009, hal. 44. Bandingkan juga Paul Torremans, Jon Holyoak, Holyoak and Torremans, Intellectual Property Law, Butterworths, London, 1998, hal. 71. Lihat juga Corynne Mc Sherry, Who Owns Academic Work ? Battling for Control of Intellectual Property, Harvard University Press, London, 2001, hal. 19. Bandingkan juga Mr. E.J. Arkenbout, Mr. P.G.F.A. Geerts, Mr. P.A.C.E. van der Kooij, Rechtspraak Intellectuele Eigendom, koninklijke vermande, Den Haag, 1997, hal. 44. 39 Di Inggris, hak cipta baru masuk dalam ranah hukum berdasarkan Keputusan Kerajaan pada tahun 1556, lihat lebih lanjut, Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 5 Walaupun sebelumnya yakni pada tahun 1476 cikal bakal perlindungan hak cipta itu telah muncul di Inggris pada saat perusahaan penerbit William Caxton memproduksi penerbitan buku untuk pertama kali kemudian diikuti pada tahun 1534 dimunculkan pembicaraan-pembicaraan tentang royalty atas pemanfaatan hak cipta oleh pihak ketiga. Terakhir mengenai perlindungan copyrights dimunculkan dalam The Statute of Anne, 8 Anne, C.19, tahun 1710. Lebih lanjut lihat Craig Joyce, et.all, Copyright Law, Second Edition, Matthew Bender, America, 1991, hal. 6. Istilah hak cipta, di Indonesia tidak dijumpai dalam literature Hukum Adat. Akan tetapi, bentuk bentuk karya cipta memang telah dikenal seperti seni tari, pencak silat, seni batik, lagu tradisional, senandung, seni lukis, seni drama, ludruk, wayang, sudah dikenal baik dalam tradisi masyarakat Indonesia. Karya-karya cipta semacam itu, belum dilindungi berdasarkan konsep dan sistem hukum seperti sekarang ini. Sehingga bentuk perlindungannya pun tidak sepenuhnya didasarkan pada norma atau sistem hukum yang baku. Masing-masing daerah ditemukan bentuk-bentuk perlindungan yang berbeda-beda. Misalnya saja jika hendak melantunkan senandung (sebuah karya seni di pesisir pantai Sumatera Timur, yang dikenal dengan Senandung Asahan) si pelantun senandung diberikan semacam kompensasi yang bernuansa religius, uang yang mirip dengan royalty itu disebut sebagai “penajam”. Jadi, instrument hukum tentang itu terjadi tanpa disengaja. Ia lahir tidak seperti lahirnya undang-undang yang memang sejak awal telah didisain dengan tujuan, kepentingan serta alasan politis tertentu. Wawancara dengan Usman, Pelantun Senandung Asahan pada tanggal 12 Juni 2013 di Desa Lubuk Besar Kabupaten Batubara. 72 dalam terminologi hukum Inggris atau Amerika. Oleh karena itu dapat dipahami (sebagai konsekuensi logis) jika di kemudian hari Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan hak cipta, pastilah itu bukan bersumber dari hukum Indonesia asli. Undang-undang itu pastilah diambil alih dari hukum asing. Mengapa Indonesia harus memiliki Undang-undang Hak Cipta sendiri ? Bagaimana jika Indonesia tidak memiliki Undang-undang Hak Cipta sendiri? Atau jika Undang-undang Hak Cipta itu sebuah keharusan, dikarenakan tuntutan kemajuan peradaban umat manusia, mengapa Indonesia tidak membuat saja Undang-undang Hak Cipta sendiri menurut model hukum Indonesia?. Model hukum yang disusun berdasarkan the original paradigmatic values of Indonesian culture and society,40 tanpa harus merujuk pada model hukum atau Undang-undang Hak Cipta asing ?. Sederet pertanyaan itu, adalah merupakan pertanyaan awal yang melatar belakangi pilihan politik hukum pembentukan Undang-undang Hak Cipta Nasional. Perlindungan terhadap hak cipta adalah perlindungan hak yang mengacu pada model yang pertama kali dikenal di belahan dunia Barat (Amerika dan Eropa Barat). Negara yang lebih dahulu maju mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi diikuti dengan kemajuan dalam dunia industeri dan perdagangan yang kesemua itu memunculkan hak-hak ekonomi (property right) mengupayakan agar hak-hak tersebut dilindungi sejarah hukum dan kemudian muncullah 40 Istilah ini diperkenalkan oleh M. Solly Lubis pada bimbingan pertama proposal (usulan disertasi ini) tanggal 12 Januari 2012. Istilah the original paradigmatic values of Indonesian culture and society kandungan dari nilai-nilai khas yang bersumber dari pandangan budaya dan bangsa Indonesia yang diwariskan oleh nenek moyang Bangsa Indonesia sejak berabad-abad yang lalu. Nilai-nilai budaya ini yang membedakan sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum yang dikenal di berbagai belahan dunia. Terdapat kombinasi dari berbagai nilai-nilai sosial dan budaya yang menurut Fred. W. Riggs, sebagai pilihan nilai prismatik. Lebih lanjut lihat Fred W. Riggs, Administration in Developing Countries : The Theory of Prismatic Society, Boston, Houghton Mifflin Company, 1964, hal. 17. Riggs, mencoba untuk mencari jalan tengah ketika mengidentifikasi pilihan kombinatif atau nilai-nilai sosial budaya yang bervariatif. Kerangka acuan yang digunakan Riggs adalah pembangunan hukum diletakkan di atas nilai-nilai sesuai dengan tahap perkembangan sosial kultur dan sosial ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Layaknya sebagai prisma, masuknya satu nilai (paradigma tunggal) akan memancarkan banyak variasi (multi paradigma). Nilai-nilai yang multi paradigma itulah untuk kasus Indonesia dipandang sebagai nilai-nilai khas atau nilai-nilai asli (the original paradigmatic values) yang bersumber dari kehidupan sosial budaya Indonesia (Indonesian culture and society) yang kemudian mengkristalkan tujuan, dasar dan cita hukum serta norma dasar negara Indonesia yang dimuat dalam Pembukaan (staatsfundamentalnorm) dan batang tubuh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 73 proteksi itu dalam bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang diwujudkan dalam bentuk aturan normatif. Barat adalah belahan dunia yang pertama kali memperkenalkan model-model proteksi hukum terhadap hasil karya ciptanya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang dikenal dengan copy rights. Kemudian setelah dunia industeri dan perdagangan berkembang muncullah hak kekayaan perindusterian (industrial property rights) meliputi; paten, merk, desain industeri, perlindungan varietas baru tanamanm perlindungan elektronik sirkuit terpadu, dan lain sebagainya. Sekalipun karya cipta atau ciptaan yang sama dikenal juga dibelahan dunia Timur, namun Timur lebih arif dalam memaknai hasil karya ciptanya, lebih bernuansa humanis dan komunal tidak berdasarkan pertimbangan prinsip individualis dan pertimbangan ekonomi semata-mata, karena itu model proteksi haknya tidak dirumuskan dalam kaedah-kaedah hukum formal yang bernuansa individualis dan kapitalis.41 Prinsip individualis dan prinsip ekonomi kapitalisme 42 telah mengantarkan Barat pada proteksi hasil karya dalam bidang ilmu 41 Erman Rajagukguk, dalam kuliahnya selama semester B pada Program Pasca Sarjana USU, dalam mata kuliah Budaya Hukum, pernah menceritakan, bagaimana seorang pembatik, lalu batiknya itu ditiru oleh orang lain, ia merasa puas jika karya ciptanya itu ditiru oleh orang lain. Sebagai pencipta ia merasa beruntung menciptakan sesuatu yang berguna bagi orang lain dan menurutnya juga ia mendapat pahala. Demikian budaya hukum yang dianut oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Budaya hukum Timur memang berbeda dengan budaya hukum Barat. Nilai-nilai individualis selalu dikesampingkan ketika berhadapan dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas. 42 Lihat Stanislav Andreski, Max Weber : Kapitalisme, Birokrasi dan Agama, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1989, hal. 52. Lihat juga Revrisond Baswir, Dilema Kapitalisme Perkoncoan, IDEA Kerjasama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hal. 29. Lihat juga Max Weber, Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, Pustaka Promethea, Surabaya, 2000, hal. 54. Bandingkan juga Francis Fukuyama, The End of History and The Last Man Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal, Qalam, Jakarta, 2003, hal. 22. Lihat juga Hernando De Soto, The Mystery of Capital Rahasia Kejayaan Kapitalisme Barat, (Terjemahan Pandu Aditya K dkk), Qalam, Jakarta, 2000, hal. 62. Bandingkan juga William J. Baumol, Robert E. Litan, Carld J. Schramm, Good Capitalism Kapitalisme Baik, Kapitalisme Buruk dan Ekonomi Pertumbuhan dan Kemakmuran, (Terjemahan Rahmi Yossinilayanti), Gramedia, Jakarta, 2010, hal. 60. Bandingkan juga Johan Norberg, Membela Kapitalisme Global, (Terjemahan Arpani), The Freedom Institute, Jakarta, 2001, hal. 84. Lihat juga David Harvey, Imperialisme Baru Genealogi dan Logika Kapitalisme Kontemporer, Resist Book, Yogyakarta, 2010, hal. 43. Lihat juga Ann Laura Stoler, Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Sumatra, 1870-1979, KARSA, Yogyakarta, 2005, hal. 55. Lihat juga Djoko Dwiyanto dan Ignas G. Saksono, Ekonomi (Sosialis) Pancasila Vs Kapitalisme Nilai-nilai Tradisional dan Non Tradisional Dalam Pancasila, Keluarga Besar Marhenisme, Yogyakarta, 2011, hal. 72. Bandingkan juga Muhammad Yunus, Bisnis Sosial Sistem Kapitalisme Baru Yang Memihak Kaum Miskin, (Terjemahan Alex Tri Kantjono), Gramedia, Jakarta, 2011, hal. 63. Lihat lebih lanjut Subcomandante Marcos, Atas dan 74 pengetahuan seni dan sastra yang dirumuskan sebagai hak cipta yang merupakan hak eksklusif atau hak khusus yang yang dilekatkan kepada pencipta atau penerima hak. Orang lain di luar pencipta tidak diperkenankan menikmati hak cipta tersebut tanpa izin penciptanya. Inilah kemudian dikembangkan di dunia Timur, setelah Barat mengalami kemajuan peradaban dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan memenangkan berbagai peperangan dan dominasi politik global yang mengalahkan Timur. Barat kemudian dikenal sebagai belahan dunia yang maju dalam peradaban ilmu pengetahuan dan teknologi yang kemudian dikenal sebagai penggagas peradaban modern. Hukum yang dikembangkan di Barat, dipandang pula sebagai hukum modern, hukum yang lebih rasional, lebih demokratis dan berkeadilan serta lebih terbuka terhadap semua lapisan masyarakat yang tidak membeda-bedakan manusia dari segi ras atau suku bangsa, serta agama dan perbedaan-perbedaan lainnya. Ketika arus gelombang modernisasi yang membawa peradaban Barat (termasuk lmu pengetahuan dan teknologi) termasuk sistem hukum itu menyeruak ke seluruh penjuru dunia termasuk ke belahan bumi Timur – tentu Indonesia berada di dalamnya - maka keharusan untuk mengikuti aturan-aturan yang dipandang modern itu, mau tidak mau harus pula diikuti. Dalam konteks ini menjadi keharusan bagi Indonesia untuk turut serta dalam keanggotaan organisasi Internasional, dan keanggotaan dalam berbagai perjanjian bilateral (dalam bentuk traktat) atau perjanjian yang bersifat regional atau internasional (dalam bentuk konvensi). Sekalipun tidak ada keterikatan secara mutlak menurut sistem hukum Indonesia terhadap perjanjian Internasional itu – meskipun Idonesia menganut teori Primat Hukum Internasional menurut faham Moechtar Koesoemaatmadja yang berarti tanpa transformasi hukum Internasional ke hukum Nasional hukum itu tetap mengikat- akan tetapi menurut Hikmahanto43 kewajiban untuk Bawah : Topeng dan Keheningan Komunike-komunike Zapatista Melawan Neoliberalisme, Resist Book, Yogyakarta, 2005, hal. 33. Lihat juga M. Daniel Nafis, Indonesia Terjajah Kuasa Neoliberalisme Atas Daulat Rakyat, Inside Press, Jakarta, 2009, hal. 46. Bandingkan juga Syafaruddin Usman & Isnawita, Neoliberalisme Mengguncang Indonesia, Narasi, Yogyakarta, 2009, hal. 58. Bandingkan juga Budi Winarno, Melawan Gurita Neoliberalisme, Erlangga, Jakarta, 2010, hal. 39. Lihat juga M. Daniel Nafis, Indonesia Terjajah Kuasa Neoliberalisme Atas Daulat Rakyat, Inside Press, Jakarta, 2009, hal. 68. Lihat juga Wim Dierckxsens, The Limits of Capitalism an Approach to Globalization Without Neoliberalism, Zed Books, New York, 2000, hal. 70. 43 Kewajiban untuk melakukan transformasi dalam perjanjian internasional yang berkatagori law making kerap diamanatkan secara tertulis. Sebagai contoh dalam Pasal XVI ayat (4) WTO Agreement disebutkan, “Each member shall ensure the 75 mentransformasikan hukum internasional ke dalam hukum nasional (untuk perjanjian Internasional yang berkatagori law making) tetap diharuskan. Jika tidak, negara-negara itu akan tertinggal. Tertinggal dalam mendapat akses ekonomi termasuk alih teknologi yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di dunia Barat, terkucil dalam pergaulan Internasional, tersisih dalam percaturan perdagangan Internasional atau terabaikan dalam proses perkembangan peradaban dunia. Oleh karena itu menurut Ningrum Natasya Sirait 44 bagi Indonesia, globalisasi yang ditawarkan oleh peradaban Barat yang sebagian besar dimotori dari - capaian Uruguay Round yang menghasilkan sistem perdagangan internasional yang tertuang dalam GATT dan WTO lebih dari sekedar keharusan untuk diikuti. Sistem perdagangan yang ditawarkan oleh GATT dan WTO hasil Putaran Uruguay tahun 1994 itu tidak hanya menyangkut perdagangan Internasional semata-mata, akan tetapi menyangkut aspek politik tata ekonomi Internasional yang baru sama sekali dan dalam implementasinya menurut Hatta melibatkan pula faktor-faktor non conformity of its laws, regulations and administrative procedures with its obligations as provided in the annexed Agreements”. Demikian pula dalam Pasal 4 ayat (1) Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment disebutkan bahwa, Each State Party shall ensure that all acts of torture are offences under its criminal law”. Mencermati ketentuan tersebut tidak bisa lain demikian menurut Hikmahanto, selain ditafsirkan adanya keharusan suatu negara untuk menterjemahkan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional suatu perjanjian internasional yang telah diikuti. Dalam uraiannya Hikmahanto mengkaji perdebatan yang sering mengemuka di Indonesia, yaitu apakah pasca keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian internasional yang berkatagori law-making harus diikuti dengan transformasi ke dalam peraturan perundang-undangan ? Beliau berpendapat bahwa untuk perjanjian internasional yang bersifat law-making maka negara memiliki kewajiban untuk menterjemahkan ke dalam peraturan perundang-undangan. Hikmahanto mengambil studi kasus atas ratifikasi dari Convention on International Interests in Mobile Equipment (Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak) beserta Prtocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment (Protokol pada Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak mengenai masalah-masalah khusus pada peralatan pesawat udara). Untuk memperluas masalah ini Indonesia meratifikasi Capetown Convention dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2007 yang telah diikuti, lebih lanjut lihat Hikmahanto Juwana, Hukum Internasional Dalam Perspektif Indonesia Sebagai Negara Berkembang, PT. Yarsif Watampone, Jakarta, 2010, hal. 85-92. 44 Lebih lanjut lihat Ningrum Natasya Sirait, Indonesia Dalam Menghadapi Persaingan Internasional, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Internasional, pada Falultas Hukum USU , tanggal 2 September 2006. 76 hukum. 45 Sistem GATT/WTO dan perjanjian ikutannya berupa TRIPs Agreement (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) berkaitan pula dengan aspek investasi yang dimuat dalam persetujuan TRIMs (The Agreement on Trade-Related Investment Measures). Investasi asing yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi itu pun menjadi terhambat, jika hak atas ciptaan (atau dalam konteks Paten merupakan temuan) mereka tidak dilindungi menurut standar perlindungan yang berlaku di negaranya. Belum lagi ancaman negaranegara maju yang tidak mau berinvestasi dan bahkan menolak izin ekspor barang-barang produksi dari negara yang masuk dalam kategori negara pelanggar hak cipta atau pembajak. 46 Itulah sebabnya kemudian mengapa Indonesia harus memiliki Undang-undang Hak Cipta yang disesuaikan dengan standar perlindungan internasional, sekalipun pada waktu itu kebutuhan undang-undang semacam itu bagi kepentingan hukum dalam negeri Indonesia bukanlah merupakan kebutuhan hukum yang mendesak. Pada mulanya, ketika Indonesia harus memiliki Undangundang Hak Cipta sendiri, pilihan politik hukum Indonesia ketika itu sangat pragmatis, dari pada membuat hukum Hak Cipta dengan model Indonesia sendiri, adalah lebih baik jika memodifikasi saja undangundang yang sudah ada yakni Auteurswet Stb No. 600 Tahun 1912. 47 Undang-undang ini memang produk Kolonial Belanda, akan tetapi 45 Lihat lebih lanjut Hatta, Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO Aspek-aspek Hukum dan Non Hukum, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hal 36 46 Kasus menarik adalah ketika eksport garmen Indonesia ditolak untuk masuk ke Amerika disekitar tahun 1990-an, karena Indonesia masuk dalam kategori negara pembajak karya hak kekayaan intelektual. Demikian juga hal yang sama diberlakukan oleh Amerika terhadap Cina, karena Cina masuk dalam kategori negara pembajak karya cipta (HKI) atau pelanggaran HKI terbesar di dunia. 47 Ini terlihat mulai dari sistematika undang-undangnya sampai pada substansinya yang tidak jauh berbeda untuk tidak dikatakan memfotocopy saja wet peninggalan Kolonial Belanda itu. Auterurswet 1912 ini diberlakukan di wilayah Hindia Belanda berdasarkan azas konkordansi. Wet ini di Negara asalnya Belanda, diperbaharui tanggal 1 November 1912 yang merupakan pembaharuan dari undang-undang hak ciptanya yang pertama yang dibuat pada tahun 1881. Pembaharuan undang-undang ini dilakukan karena Kerajaan Belanda sama dengan Negara-negara di kawasan Eropa Barat lainnya, telah mengikatkan dirinya dalam Konvensi Bern 1886. Setelah Kerajaan Belanda memperbaharui Undang-undang Hak Cipta tahun 1881 dengan Auteurswet 1912 Kerajaan Belanda kemudian mengikatkan dirinya pada tanggal 1 April 1913 dalam keanggotaan Konvensi Bern 1886. Tentu saja sebagai daerah jajahan, keikutsertaan Belanda dalam konvensi ini menyebabkan Indonesia diikutsertakan pada konvensi tersebut dengan didaftarkannya dalam Staatblad 1914 No. 797. Lebih lanjut lihat, Suyud Margono, Op.Cit, hal. 53-54. 77 pilihan kebijakan legislasi Indonesia – karena sejak awal belum dianggap sebagai kebutuhan mendesak – membiarkan begitu saja berlaku “wet” ini di negara Indonesia Merdeka sampai dengan kurun waktu 70 tahun. Baru pada tahun 1982 ada gagasan untuk merobah undang-undang ini menjadi undang-undang yang lebih bernuansa Indonesia, atau mengacu pada prinsip hukum yang original paradicmatic values of Indonesian culture and society. 48 Terjadinya perubahan itu adalah karena tuntutan perkembangan zaman yang di dalamnya berisi muatan politik, ekonomi dan muatan sosio-kultural lainnya yang terus berubah sebagai akibat dari capaian kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 49 Pada zaman Hindia Belanda, Kolonial Belanda memandang perlu diadakannya instrumen hukum yang memberikan perlindungan kepada pencipta terhadap hasil karyanya. Seperti telah diungkapkan di atas, diundangkanlah dalam Stb. 1912 No. 600 instrumen hukum yang melindungi karya cipta tersebut yang dikenal dengan Auteurswet. Sampai masa kemerdekaan “wet” itu terus berlaku – tentu saja berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ketika itu – hingga Tahun 1982 diundangkan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 15 Tahun 1982 tanggal 12 April 1982 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3217 mencabut Staatblad 1912 No. 600 tersebut tentang Auteurswet.50 Persoalan kedua, adalah persoalan pergeseran nilai-nilai filosofis dalam pembentukan Undang-undang Hak Cipta Nasional yang menggunakan pilihan politik pragmatis dengan model transplantasi hukum. Isi dari undang-undang seyogyanya (das Sollen) harus mampu menangkap semua harapan, ide, cita-cita hukum masyarakat Indonesia yang berisikan the original paradicmatic value of Indonesian culture and society (das Wollen), yang dirumuskan dalam ideologi negara sebagai dasar falsafah negara yakni Pancasila sebagai grundnorm yang kemudian diturunkan sebagai tata nilai atau asas-asas hukum untuk kemudian dijelmakan ke dalam norma hukum konkrit. 48 Lihat BPHN, Seminar Hak Cipta, Binacipta, Jakarta, 1976 , hal. 82. Perubahan pada cara pandang tentang kehidupan (philosophy of life, akan merubah sistem hukum yang dipilih, lihat Jack M. Balkin, The Laws of Change, Sybil Creek Press, Toronto-Canada, 2009 , hal. 72. Lihat juga lebih lanjut, Michael B. Gerrard (ed), Global Climate Change and US Law, ABA Publishing, Chicago, 2007, hal. 105, Bagaimana perubahan iklim global yang sebenarnya adalah perubahan fisik iklim bumi, turut mempengaruhi perubahan hukum di Amerika Serikat. 50 Walaupun substansinya hampir dapat dipastikan masih sama dan senada dengan Auteurswet Stb. 600 Tahun 1912. 49 78 Keharusan untuk melakukan perubahan perangkat hukum hak cipta itu terjadi tidak terlepas dari tuntutan dan pengaruh internal yang sesungguhnya tidak begitu dominan jika dibandingkan dengan tuntutan eksternal yang berasal dari negara luar sebagai tuntutan arus perubahan zaman dan kemajuan peradaban umat manusia yang dikenal dengan globalisasi. Bagi Indonesia, selaku negara yang berdaulat, yang masuk dalam kelompok negara-negara berkembang yang posisinya tidak sama dengan 8 negara ekonomi maju atau disingkat G-8 (Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Rusia, Britania Raya dan Amerika Serikat) sejatinya harus mampu “menyaring” kepentingan asing yang dominan (dominasi politik dan ekonomi asing) yang dimasukkan dalam peraturan Undang-undang Hak Cipta Nasional. Harapan, ide-ide, gagasan yang berisikan dan bercirikan Indonesia atau the original paradicmatic values of Indonesian culture and society, adalah bahagian penting yang harus dituangkan dalam pilihan kebijakan transplantasi hukum hak cipta. Legal transplants 51 atau legal borrowing, atau legal adoption demikian istilah yang diperkenalkan oleh Alan Watson, 52 untuk 51 Pilihan terminologi legal transplants bermula dari mengikuti perkuliahan Ningrum Natasya Sirait selama kurun waktu Semester Ganjil TA 2011-2012 dalam mata kuliah Perbandingan Sistem Hukum. Beliau memperkenalkan buku yang ditulis oleh Alan Watson yang berjudul “Legal Transplants An Approach to Comparative Law” terbitan Scohish Academic Press, Amerika, Tahun 1974. Membaca naskah ini, menyebabkan judul disertasi yang semula “Pengadopsian Hukum Asing” berubah pilihannya menjadi Transplantasi Hukum. Terminologi hukum (rechts terminologie) tentang transplantasi hukum digunakan oleh para ilmuwan hukum untuk menyebutkan sebuah kebijakan negara yakni, pengambilalihan hukum asing untuk dijadikan hukum di negara sendiri. Ada banyak istilah yang digunakan untuk menyebutkan peristiwa itu, mulai dari istilah meminjam hukum asing, mengadopsi, migrasi hukum, translokasi sampai pada istilah kolonisasi hukum asing dan ada lagi yang menggunakan istilah okulasi. Sebut saja istilah legal receptions yang dikemukakan oleh Loukas A. Mistelis dan Moh. Koesnoe, legal borrowing atau legal adoption yang dikemukakan oleh Alan Watson sebelum ia sampai pada istilah legal transplants, legal migration istilah ini digunakan oleh Katharina Pistor, legal colonization ini adalah istilah yang digunakan Galanter, translocation of law ini adalah istilah yang diperkenalkan oleh Antony Allott, legal surgery sebuah istilah yang dikemukakan oleh Loukas A. Mistelis, legal transposition dikemukakan oleh Esin Orucu, legal change yang dikemukakan oleh Haim H. Cohn, Lihat Julius Stone, Legal Change Essays in Honour of Julius Stone, Blackshield, Butterworths Pty Limited, Australia, 1983, hal. 56. Bahkan Roscoe Pound pernah menggunakan istilah “assimilation of materials from outside of the law”, untuk menyebutkan rangkaian proses transplantasi hukum itu. Lebih lanjut lihat Tri Budiyoni, Transplantasi Hukum Harmonisasi dan Potensi Benturan Studi Transplantasi Doktrin Yang Dikembangkan dari Tradisi Common Law pada UU PT, Griya Media, Salatiga, 2009 , hal. 124, hal. 4. Guru besar ilmu hukum dari Delf Universiteit yang bernama : Mr. W. C. Van Den Berg yang juga penasehat bahasa-bahasa Timur dan Hukum Islam pada 79 menyebutkan suatu proses meminjam atau mengambil alih atau memindahkan hukum dari satu tempat atau dari satu negara atau dari satu bangsa ke tempat, negara atau bangsa lain kemudian hukum itu diterapkan di tempat yang baru bersama-sama dengan hukum yang sudah ada sebelumnya. Transplantasi hukum itu dapat juga terjadi karena keharusan untuk mentransfromasikan perjanjian Internasional (perjanjian dalam bentuk law making), karena Indonesia turut serta sebagai anggota konvensi Internasional itu. 53 Kasus semacam ini dapat dilihat pada kasus tranformasi ketentuan GATT/WTO dan perjanjian ikutannya seperti TRIPs Agreement yang menjadi dasar transplantasi peraturan perundang-undangan HKI Indonesia, dan Kesepakatan TRIMs yang menjadi dasar transplantasi peraturan perundangundangan tentang Penanaman Modal Asing, demikian juga beberapa konvensi Internasional tentang lingkungan hidup dijadikan dasar bagi penyusuanan peraturanperundang-undangan tentang Lingkungan Hidup di Indonesia. Di samping itu transplantasi hukum dapat juga terjadi karena adanya koloni atau aneksasi atau imperialis oleh satu negara atas negara lain. Untuk kasus Indonesia, koloni yang dilakukan oleh Pemerintah Belanda telah “memaksa” Indonesia untuk melakukan penyesuaian hukum peninggalan Kolonial Belanda ke dalam hukum Nasional Indonesia yang merupakan cikal bakal transplantasi. Dalam keadaan damai tanpa peperanganpun transplantasi hukum itu terus berlangsung, mengikuti kemajuan peradaban umat manusia, karena kemajuan peradaban akan menimbulkan hubunganpemerintahan Hindia Belanda, pernah meneliti hukum adat di Indonesia dan melahirkan teori yang sangat terkenal yaitu teori ”Receptio in Complexu”. Inipun sebenarnya masih bercerita tentang terma transplantasi hukum Islam (hukum agama) ke dalam hukum adat, bahkan kata Berg, seluruh hukum Islam diresepsi oleh hukum adat. Selama bukan sebaliknya kata Berg menurut ajaran ini hukum pribumi ikut hukum agamanya sekalipun jika ia berpindah agama ia-pun juga harus mengikuti hukum agamanya dengan setia. Lihat Sajuti Thalib, Politik Hukum Baru Mengenai Kedudukan dan Peranan Hukum Islam Dalam Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta, Jakarta, 1987, hal. 51. Namun pendapat ini ditentang oleh Hazairin, dia mengatakan tidak semua hukum adat itu diresepsi dari hukum Islam, lihat lebih lanjut Hazairin, Tujuh Serangkai Tentang Hukum, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 44. Intinya Berg mempergunakan istilah receptio untuk term transplantasi. 52 Alan Watson, Legal Transplants An Approach to Comparative Law, Scottish Academic Press, America, 1974, hal. 22. Dengan meminjam pandangan Roscoe Pound Watson menulis “… and Roscoe Pound could write : “History of a system of law is largely a history of borrowings of legal materials from other legal systems and of assimilation of materials from outside of the law”, bandingkan Tri Budiyoni, Ibid, hal. 25; Gunawan Widjaja, Transplantasi Trusts dalam KUH Perdata, KUHD dan Undangundang Pasar Modal Indonesia, Rajawali, Jakarta, 2008, hal. 35 s/d 38. 53 Lebih lanjut lihat Hikmahanto Juwono, Op.Cit, hal 85. 80 hubungan hukum yang baru yang tidak dikenal sebelumnya. Negara yang menemukan hasil peradaban baru tersebut akan menyediakan pula instrumen hukum baru guna mengatur hubungan atau peristiwa hukum yang baru atas temuan hasil peradaban yang baru itu. Tentu saja hukum yang baru itu akan ikut masuk ke negara lain bersamaan dengan hasil temuan dari peradaban tersebut. Sebagai contoh, ketika transaksi keuangan dapat dilakukan secara on-line sebagai akibat kemajuan peradaban dalam bidang teknologi informasi, maka hukum yang mengatur tentang itu harus ditransplantasikan dari negara yang pertama sekali menggunakan transaksi keuangan secara on-line itu. Dampaknya tidak hanya terhadap hukum perbankan, akan tetapi juga terhadap hukum pidana yang berkaitan dengan pencucian uang. Demikian seterusnya transplantasi hukum itu akan terus berlangsung tanpa henti seperti yang dikatakan oleh Watson dengan mengutip Esin Orucu, 54 ia sampai pada satu kesimpulan : “Transplantasi hukum itu masih ada dan akan terus hidup dengan baik sebagaimana juga halnya pada masa Hammurabi. 55 Lebih lanjut Esin Orucu mengatakan : What is regarded today as the theory of ‘competing legal systems’, albeit used mainly in the rhetoric of ‘law and economics’ analysis, was the basis of the reception of laws that formed the Turkish legal system in the years 1924 - 1930. The various Codes were chosen from what were seen to be ‘the best’ in their field for various reasons. No single legal system served as the model. The choice was driven in some cases by the perceived prestige of the model, in some by efficiency and in others by chance. 56 Orucu berkesimpulan, tidak ada satu sistem hukum yang tunggal yang dijadikan model pembangunan hukum di berbagai negara. Dengan mengambil contoh pada masyarakat Turki, Orucu menjelaskan bahwa Turki pasca runtuhnya dinasti Osmania telah mengambil banyak sistem hukum yang dijadikan model bagi pembangunan hukum di negerinya. Hukum pidana dan hukum perdata diambil dari Swiss, sedangkan hukum administrasi negara diambil dari model hukum Prancis. Dengan memilih berbagai model hukum, melalui kebijakan 54 Alan Watson, Loc.Cit , hal. 5. M.E.J. Richardson, Hammurabi’s Laws Text, Translation and Glossary, T & T International, New York, 2004. 56 Alan Watson, Legal Transplants and European Private Law, University of Belgrade School of Law, Pravni Fakultet, Belgrade, 2006, hal. 6-7. Lihat juga Esin Orucu, The Enigma of Comparative Law, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston, 2004, hal. 26. 55 81 transplantasi kata Orucu Turki di bawah rezim Mustafa Kemal AlTaturk, berhasil meletakkan politik hukum transplantasi menjadi alat legitimasi budaya, karena pada akhirnya model hukum yang dipilih tidak terikat pada salah satu budaya yang dominan. Itulah yang oleh Orucu disebutnya sebagai sistem campuran dan itu tumbuh karena adanya mobilitas sosial dalam masyarakat yang dapat terjadi karena ekspansi oleh satu negara ke negara lain, karena pendudukan (aneksasi), penjajahan atau dalam bentuk suatu upaya modernisasi yang dipaksakan. Bentuk lain dari sistem campuran itu terjadi karena penyerapan norma hukum asing secara sukarela (untuk kasus Indonesia misalnya penyerapan norma hukum Islam), infiltrasi atau inspirasi dan imitasi sebagai wujud dari perubahan dalam struktur sosial sebagaimana diuraikan oleh Orucu 57 berikut ini : Mixed and mixing systems and the migration of legal institutions are two inseparable fields of study. The fact that law is not static lies at the bottom of all mixed systems. Moving populations add another dimension to this phenomenon. The coming into being of mixed jurisdictions is one of the outcomes of mobility of law and mobility of peoples. Law moved across boundaries. The simplest, most easily defined and understood forces behind these movements are expansion, occupation, colonization and efforts of modernization, and the ensuing impositions, imposed receptions, voluntary receptions, infiltrations, inspirations and imitations and concerted or co-ordinated parallel developments. Legal ideas, concepts, structures and rules move from legal order to legal order along these paths. In such movement there is interference with the horizontal logic (internal symmetry) and the vertical logic (the typical pattern of unfolding) of legal systems or legal orders, sometimes creating confusion, after which the legal systems settle into mixed jurisdictions or hybrid systems. Untuk kasus Indonesia, mengambil sistem hukum yang berasal dari negara lain yang dikembangkan menjadi model hukum di negeri sendiri, bukanlah sesuatu yang baru. Asas konkordansi yang dipilih sebagai politik hukum Indonesia pada masa Hindia Belanda dan terus dikembangkan pada masa kemerdekaan adalah salah satu contoh saja untuk menggambarkan keadaan itu, bahwa sesungguhnya mengambil model hukum asing untuk dijadikan model hukum di negeri sendiri adalah suatu yang lumrah dan tidak terlalu buruk untuk 57 Esin Orucu, Elspeth Attwooll & Sean Coyle, Studies in Legal Systems : Mixed and Mixing, Kluwer Law International, London/Boston, 1996 , hal. 341. 82 dilakukan. Transplantasi hukum terus berlangsung berawal dari zaman pra Kolonial Belanda, hingga sekarang, 58 mulai dari menggantikan posisi hukum Indonesia asli (hukum adat dan kebiasaan yang original) sampai pada masuknya kaedah hukum yang baru sama sekali, yang belum dikenal dalam peradaban (hukum) Indonesia. Demikian pula halnya dengan keberhasilan Indonesia dalam melahirkan Undang-undang Hak Cipta, mulai dari Undang-Undang No.6 tahun 1982 sampai dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2002, melalui kebijakan transplantasi undang-undang peninggalan Kolonial Belanda sampai dengan TRIPs Agreement hasil Putaran Uruguay Dengan politik transplantasi itu hasilnya adalah, paling tidak saat ini Indonesia telah mempunyai perangkat hukum hak cipta yang memenuhi standar internasional, standar yang diisyaratkan GATT/WTO 1994 seperti yang termaktub dalam TRIPs Agreement, walaupun ternyata dikemudian hari pelaksanaan undang-undang ini banyak menuai kritik. Kebijakan dalam bidang legislasi melahirkan undang-undang hak cipta nasional hampir tak pernah bebas dari kritik, terutama dalam hal substansi dan penegakan hukum (law enforcement)nya. Kenyataan sesungguhnya, bahwa undang-undang itu, gagal mencapai tujuannya. Gagal dalam merumuskan ide-ide dan cita-cita negara, gagal dalam menciptakan kepastian hukum dan bahkan gagal dalam pencapaian cita-cita kesejahteraan melalui perlindungan optimal atas hasil karya cipta. Dalam bahasa yang sederhana undang-undang ini gagal mentransformasikan landasan ideologis/filosofis Pancasila ke dalam Undang-undang Hak Cipta Nasional. Pengaruh ideologis/filosofis asing masuk mewarnai undang-undang ini. Para legal (ahli hukum) gagal menjadikan Pancasila sebagai ideologi “penyaring” ketika kebijakan transplantasi hukum dilangsungkan dalam pembentukan Undang-undang Hak Cipta Nasional. Kejadian ini tidak satu kali, tapi beberapa kali terulang di sepanjang sejarah perubahan Undang-undang Hak Cipta. Apakah ini pertanda bahwa bangsa ini tak pernah memiliki sikap kehati-hatian dalam menerapkan kebijakan transplantasi hukum ? Kehati-hatian dalam melakukan transplantasi hukum asing ke dalam hukum Indonesia khususnya dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual diingatkan oleh Candra Irawan dan 58 Pada masa Hindu, hukum Hindu turut mewarnai hubungan-hubungan hukum yang berlangsung dalam masyarakat di wilayah nusantara ketika itu, demikian juga ketika Islam masuk ke Indonesia, Hukum Islam turut pula mewarnai perkembangan hukum ketika itu. Dengan begitu benarlah ungkapan Roscoe Pound, sejarah sistem hukum adalah sejarah meminjam dan assimilasi materi hukum dari sistem hukum lain. 83 Budi Agus Riswandi. 59 Beberapa hal yang dapat dipetik dari pandangan mereka berdua, adalah : 1. Indonesia harus hati-hati mengadopsi The Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs) ke Undangundang Hak Kekayaan Intelektual. 2. Dalam transplantasi harus diperhatikan kepentingan nasional. 3. Ada kesan dipaksakan upaya penyesuaian pembentukan Undangundang Hak Kekayaan Intelektual dengan The Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights. 4. Aspek kepentingan nasional tak terlihat dalam proses transplantasi itu meskipun kepentingan nasional itu dimasukkan dalam konsiderans tapi dalam normanya tak mencerminkan jiwa (landasan filosofis/ideologis) ke Indonesiaan. 5. Kepentingan asing terlalu dikedepankan sehingga perangkat hukum Hak Kekayaan Intelektual menjadi tidak bermakna bagi kepentingan nasional. 6. Secara kultural tata kehidupan bangsa Indonesia bersifat komunal bukan individualistik, The Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights mengedepankan kultur individualistik, yang sudah barang tentu tak sesuai dengan kultur bangsa Indonesia Kebijakan pembangunan suatu bangsa dapat saja mengacu atau meniru pada format pembangunan yang dilakukan oleh bangsa lain. Pembangunan ekonomi, pendidikan, infrastruktur, pembangunan industeri strategis, industeri manufactur, industeri kelautan, industeri otomotif, industeri transpostasi , industri informasi dan lain sebagainya dapat dicontoh dari model-model yang dikembangkan oleh bangsa lain, namun itu tidak berlaku sepenuhnya untuk pembangunan hukum. Teori yang dikemukakan Robert B. Seidman 60 yaitu The Law of Non Transferability of Law menyimpulkan bahwa, hukum suatu bangsa tidak dapat diambil alih begitu saja, tanpa harus mengambil alih aspekaspek yang mengitari (aspek sosial budaya) tempat di mana hukum itu berpijak (diberlakukan). Teori ini justeru lahir dari hasil penelitian Seidman bersama rekannya William J. Chambliss disebuah negara di Afrika Selatan bekas jajahan Inggeris. Segera setelah Inggeris meninggalkan negara jajahannya, hukum Inggeris yang ditinggalkan, tidak mampu menjalankan fungsinya, sebab faktor sosial budaya masyarakat Afrika 59 Lihat lebih lanjut Candra Irawan, Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 14 s/d 22. 60 Robert B. Seidman, The State, Law and Development, St. Martin's Press, New York, 1978, hal. 29. 84 Selatan berbeda dengan socio-cultural bangsa Inggeris. Demikian juga di tempat-tempat lain seperti di Turki, Etiopia dan koloni-koloni Perancis di Afrika dan juga di Indonesia, hukum asing itu berhasil ditransplantasikan dalam hal substansinya tapi gagal dalam penerapannya karena faktor-faktor perbedaan pada kultur dan struktur sosialnya seperti; hubungan sosial, ekonomi, politik, birokrasi pemerintahan dan birokrasi lembaga penegakan hukum dan faktorfaktor fisik dan faktor subyektif lainnya seperti kebiasaan masyarakat setempat dan lain sebagainya. Di berbagai negara faktor-faktor seperti : geografi, histori, kemajuan teknologi-pun cukup signifikan juga mempengaruhi kegagalan penerapan hukum yang normanya berasal dari transplantasi hukum asing seperti yang diungkapkan oleh Robert B. Seidman dan Ann Seidman : Turkey copied French law, Ethiopia copied Swiss law, the French speaking African colonies, French law, Indonesia, Dutch law. Universally, these laws failed to induce behavior in their new habitats anything like that in their birtplaces. Inevitably, people chose how to behave, not only in response to the law, but also to social, economic, political, physical and subjective factors arising in their own countries from custom, geography, history, technology and other, non-legal circumstances.61 Mengacu pada pandangan di atas, sudah saatnya Indonesia dalam kebijakan pembangunan hukumnya, memperhatikan dan mempertimbangkan faktor sosio-kultural, sebab meminjam istilah Satjipto Rahardjo, hukum tidak berada pada ruang hampa, tapi ia berada bersama-sama sub sistem sosial lainnya, dalam sistem sosial yang lebih luas. M. Solly Lubis, juga menegaskan hukum itu hanya merupakan salah satu sub sistem saja dalam sistem nasional. Masa depan hukum itu ditentukan oleh pilihan kebijakan politik hukum. 62 61 Lihat Ann Seidman dan Robert B. Seidman, State and Law in The Development Process Problem-Solving and Institutional Change in the Third World, St. Martin’s Press, 1994, hal. 44. 62 Lihat Satjipto Rahardjo, Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, Genta Publishing, Jakarta, 2009, hal. 45. Lihat lebih lanjut ; Satjipto Raharjo, Hukum Progrresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Genta Publishing, Jakarta, 2009, hal. 58. Bandingan juga Satjipto Rahardjo, Membangun dan Merombak Hukum Indonesia Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 62 dan M. Solly Lubis, SH, Sistem Nasional, Mandar Maju, Bandung, 2002, hal. 71. Bandingkan dengan pandangan M. Solly Lubis yang menempatkan hukum dalam sistem politik bersamasama dengan sub sistem nasional lainnya dalam satu sistem yang disebutnya sebagai SISNAS. M. Solly Lubis, Serba-Serbi Politik & Hukum, Edisi 2, PT. Sofmedia, Jakarta, 85 Penyusunan materi hukum (aspek substantif menurut Friedman) oleh lembaga legislatif, bukanlah bebas dari pengaruh eksternal. Legislatif dalam menjalankan fungsi legislasinya, pastilah mendapat pengaruh dari luar, baik secara kelembagaan maupun secara individual. Demikianlah pula dalam hal proses ”law enforcement” aparat judikatifpun tidak bebas dari pengaruh-pengaruh seperti yang dialami oleh legislatif. Akhirnya hukum yang dihasilkan selalu dirumuskan sebagai resultant dari kekuatan tarik menarik tersebut. Pandangan yang sama dikemukakan juga oleh Harold J. Laski, bahwa pada akhirnya hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat itu adalah hukum yang merupakan hasil kekuatan tarik menarik berbagai kepentingan politis, baik pada saat pembuatannya maupun pada saat penerapannya. Laski menyebut hasil akhir itu sebagai resultan, mirip bekerjanya perkalian dua vektor dalam ilmu mate-matika, seperti skema perkalian dua vektor di bawah ini : 63 Skema 1 Resultan Kekuatan Tarik Menarik Dalam Politik Hukum R a b a = vektor a b = vektor b R = Resultant (hasil perkalian vektor a x vektor b) 2011, hal. 65. Demikian juga uraian-uraian kuliah dalam M. Solly Lubis, sepanjang Semester Ganjil TA 2011-2012 dalam mata kuliah SISNAS pada Program Pasca Sarjana USU. 63 Robert B. Seidman, Op.Cit, hal. 75, lihat lebih lanjut Harold J. Laski, Reflections on The Revolution of Our Time, Transaction Publishers, New Brunswick (USA) and London (UK), 2012, hal. 65. Harold J. Laski mengatakan hasil akhir dari hukum adalah resultant dari kekuatan tarik-menarik itu. Lihat juga Harold J. Laski, Studies in Law and Politics, Transaction Publisher, New Jersey, 2010, hal. 63. 86 Khusus dalam bidang hak cipta, Undang-undang No. 19 Tahun 2002 adalah hasil (resultant) dari berbagai faktor atau kekuatan tarik menarik baik secara internal maupun eksternal dalam institusi negara (tekanan dalam negeri dan internasional) maupun pengaruh internal dan eksternal institusi legislatif dan judikatif dalam negara Indonesia sendiri baik bersifat kelembagaan maupun perorangan. Meminjam skema yang dikembangkan oleh Seidman, bekerjanya berbagai faktor non hukum sebagai kekuatan tarik menarik itu dapat disederhanakan dalam skema sebagai berikut : 87 88 Dengan meminjam kerangka analisis Robert B. Seidman dan Laski, maka keberadaan hukum Indonesia hari ini, adalah merupakan hasil akhir dari hukum yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia atau hasil (resultant) dari kekuatan tarik-menarik (antar vektor) dari tiap-tiap faktor (politik dan non politik) yang mempengaruhinya. 64 Faktor tekanan (politik-ekonomi) internasional adalah faktor yang menjadi kekuatan politik dalam pembentukan Undang-undang Hak Cipta Nasional. Keberadaan Indonesia dalam keanggotaan General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 1994/World Trade Organization (WTO), telah mewajibkan Indonesia untuk meratifikasi hasil putaran General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 1994/World Trade Organization (WTO) tersebut, yang salah satu capaian kesepakatan itu adalah instrumen (figur) hukum TRIPs (The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights). Dalam tulisannya, Ganguli menyebutkan : ”The TRIPs agreement provides considerable room for its Members to implement the provisions and achieve a proper balance of various domestic/national interests”. 65 Konsekuensinya dalam bidang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Convention sebagai salah satu capaian dari Putaran General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 1994/World Trade Organization (WTO) tersebut, beserta konvensi-konvensi ikutannya seperti Bern Convention dan Rome Convention (1961) wajib juga diratifikasi. Setelah Indonesia meratifikasi GATT/WTO 1994, melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1994, Indonesia menjadi terikat secara hukum (tentu juga secara moral) dengan kesepakatan internasional itu. Sebagai konsekuensinya Indonesia harus menyesuaikan peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual-nya dengan Konvensi Internasional tersebut. Inilah yang kemudian mengantarkan Indonesia harus mengalami beberapa kali merubah peraturan perundangundangan Hak Kekayaan Intelektual-nya, termasuk Hak Cipta. 64 Bandingkan dengan pendapat Harold J. Laski, Studies in Law and Politic, Transaction Publisher, New Jersey, 2009, hal. 68, bahwa kekuatan tarik menarik antara secara politik hukum, akan mempengaruhi hasil akhir pembentukan hukum. Lihat juga (economic dan hukum) Robert Cooter dan Thomas Ulen, Law And Economics, Wesley Educational Publishers Inc., California, 1997 dan Eric A. Posner, Law and Economics, Foundation Press, New York, 2000 , hal.125. 65 Lebih lanjut lihat, Prabuddha Ganguli, Intellectual Property Rights Unleashing the Knowledge Economy, Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, New Delhi, 2001, hal. 59. 89 Persoalan ketiga adalah, ketika undang-undang hasil transplantasi itu diterapkan, ternyata mendapat penolakan. Dalam bidang perlindungan karya sinematografi, undang-undang itu tak cukup mampu atau tidak efektif untuk melindungi hak-hak para pencipta. Seyogyanya (das Sollen) ketika undang-undang selesai disusun dan siap untuk diterapkan, semestinya dapat diterapkan dan mampu mencapai tujuannya. Karya sinematografi adalah salah satu ciptaan (dari 12 ciptaan) yang dilindungi menurut Undang-undang Hak Cipta Indonesia. Karya sinematografi didalamnya tidak hanya menyangkut karya dalam bidang seni dan sastra tetapi juga mencakup bidang ilmu pengetahuan. Karya sinematografi dalam film dokumenter dan liputan tentang fenomena alam, kegiatan makhluk hidup dan aktivitas bumi dan planet-planet lain, tidak sedikit memperlihatkan banyaknya pesan keilmuan yang ditampilkannya secara visual. Demikianlah karya sinematografi memadukan unsur seni dan sastra baik alur cerita yang dipetik dari novel, lagu-lagu dan musik yang ditampilkan, sampai pada penataan artistik, semua terhimpun dalam karya sinematografi. Pendek kata, karya sinematografi mencakup keseluruhan dari obyek hukum yang dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta, yakni karya ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusasteraan. 66 Transplantasi hukum yang bersumber dari hukum asing itu telah berwujud dalam bentuk Undang-undang Hak Cipta Nasional, undang-undang yang terakhir adalah Undang-undang No. 19 Tahun 2002. Undang-undang itupun telah diterapkan di seantero jagad Indonesia, mulai dari Aceh sampai ke Papua. Banyak peristiwa yang tercatat dan tak tercatat dalam penegakan hukum Hak Cipta, dalam bidang karya sinematografi. Segera setelah Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 diberlakukan, Indonesia diperkirakan akan memiliki instrumen hukum yang setara dengan negara maju. Dengan kata lain, jika suatu saat investasi asing masuk ke Indonesia mensyaratkan adanya proteksi terhadap karya cipta asing, maka secara juridis Indonesia tidak lagi harus mengalami kesulitan. Standar perlindungan Hak Cipta di Indonesia telah sama dan setara dengan negara maju di dunia. Sebab, demikian menurut Candra Irawan, 67 Indonesia tidak hanya memenuhi 66 Ini adalah salah satu alasan penting mengapa kami memilih karya sinematografi menjadi obyek penelitian dalam disertasi ini disamping karena belum banyak disertasi yang memilih tema ini sebagai obyek penelitian. 67 Lihat Candra Irawan, Op.Cit, hal. 316. Beliau mengatakan pengadopsian TRIPs ke dalam HKI Indonesia, tidak melalui harmonisasi hukum yang baik. Aspirasi Pancasila, kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Pancasila dan UUD ’45 dan realitas 90 persyaratan minimal sebagaimana diisyaratkan oleh General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 1994/World Trade Organization (WTO), akan tetapi telah memberikan syarat yang optimal. Capaian lembaga legislasi untuk melahirkan Undang-undang Hak Cipta Nasional patut dihargai, karena betapapun juga dengan segala keterbatasannya lembaga itu telah bekerja untuk menghasilkan instrumen hukum perlindungan Hak Cipta, meskipun dalam kenyataan empirik memperlihatkan instrumen hukum itu tidak efektif daya lakunya. Sebut saja pembajakan karya sinematografi melalui Video Compact Disc. Di mana-mana tempat penjualan Video Compact Disc di Kota Medan satu keping Video Compact Disc dijual dengan harga Rp. 3.000 s/d Rp. 5.000,- per keping. Padahal barang yang sama jika dibeli di toko Video Compact Disc di Singapura dijual dengan harga 7 s/d 10 dollar Singapura atau setara dengan Rp. 60.000,- s/d Rp. 70.000,- per keping. Ini memperlihatkan betapa kepingan Video Compact Disc itu dijual dengan harga yang relatif murah di pasar-pasar modern dan tradisional di Kota Medan. Hal ini terjadi karena kepingan Video Compact Disc itu diproduksi tidak dengan membayar royalty kepada produser dan pencipta atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi. Masyarakat konsumen sendiri bukannya tidak pernah memahami aturan itu. Kepingan Video Compact Disc dijual dan dipasarkan melalui ”hukum permintaan” pasar. Di mana harga murah ke sanalah mereka akan berbelanja. Budaya hukum Indonesia belum terbiasa dengan model proteksi hukum hak cipta berdasarkan Undangundang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002. Jika diukur tingkat efektivitas keberlakuan Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 di tengahtengah masyarakat, khususnya dalam hal perlindungan karya sinematografi, dapat diasumsikan efektivitas keberlakuan Undangundang Hak Cipta dalam hal perlindungan karya sinematografi masih rendah. Menyangkut dampak globalisasi terhadap keberadaan Undang-undang Hak Cipta. Globalisasi telah mempengaruhi banyak negara di dunia melakukan pilihan kebijakan transplantasi hukum sebagai pilihan politik hukumnya. Meratifikasi TRIPs Agreement sebagai salah satu hasil dari Putaran Uruguay Round yang menghasilkan General Agreement on Tariff and Trade (GATT) sosial bangsa Indonesia juga belum terakomodasi dengan baik, padahal ada peluang yang dibuka oleh TRIPs untuk itu. 91 1994/World Trade Organization (WTO) adalah pilihan politik hukum yang ditempuh Indonesia sebagai dampak dari globalisasi ekonomi tersebut. Pilihan politik hukum ini membawa dampak pula terhadap eksistensi hukum (Undang-undang Hak Cipta Nasional). Hak Cipta yang meliputi ilmu pengetahuan, seni sastra termasuk sinematografi tidak tumbuh secara linier dari Barat mengalir ke Timur, tetapi tumbuh secara sporadis di berbagai belahan bumi. Tumbuh seperti jamur di hutan belantara, tidak hanya putih, tapi juga merah, kuning, jingga bahkan ada yang hitam. Ilmu pengetahuan, seni dan sastra tumbuh penuh dengan warna-warni. Akan tetapi hukum yang mengaturnya tumbuh secara linier, tumbuh menurut alam pikiran ”Barat” yang – materialis – liberal - mengalir masuk ke belahan bumi Timur. The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) sebagai produk hukum yang penuh dengan warna Barat – yang liberal – individualis – materialis masuk ke belahan bumi Timur lewat ratifikasi, lalu kemudian Timur yang turut dalam anggota konvensi, harus menyesuaikan peraturan perundang-undangan HKI-nya (termasuk Hak Cipta) dengan tuntutan The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) sebagai produk hukum yang lahir dari dan atau dominasi peradaban Barat yang dikenal dengan General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 1994/World Trade Organization (WTO). 68 Inilah salah satu dampak globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi yang membawa dampak pada kebijakan politik hukum Indonesia, yang pada gilirannya berdampak pula terhadap substansi hukum peraturan perundang-undangan Hak Cipta Indonesia yang salah satu diantaranya adalah perlindungan karya sinematografi. Tradisi wayang, yang ditayangkan dari satu pesta ke pesta lain, dari dalang yang satu ke dalang yang lain, dari sinden satu ke sinden lain dalam satu cerita wayang yang sama, telah membentuk budaya hukum, bahwa tak ada pelanggaran hak yang dilakukan dalam peristiwa itu. Akan tetapi dengan adanya Rome Convention Tahun 1961 yang memperkenalkan adanya ”Neighbouring Rights” hak siaran atau 68 Kita tidak hendak mempersalahkan “Barat” dalam usahanya untuk menyatukan visi dan misi perekonomian dunia lewat peraturan hukum globalisasi General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 1994/World Trade Organization (WTO) akan tetapi, kenyataan ini menjadi pembelajaran sejarah, pembelajaran politik, bagi Indonesia yang belum “cair” pemahamannya tentang perlunya mempertahankan jati diri bangsa. Tentang perlunya mempertahankan the original paradicmatic of Indonesian values cultural and society, perlunya mempertahankan ideologi bangsa, ideologi negara yakni Pancasila yang sudah dipilih oleh pendiri bangsa dan negara ini sebagai sumbersumber nilai kehidupan berbangsa dan bernegara, sumber-sumber hukum. 92 menggunakan tampilan orang lain, tanpa izin adalah sebuah perbuatan hukum pelanggaran hak yang juga dapat dikenakan pembayaran royalty dan penyiaranya harus mendapat izin dari pemegang hakya. Faktor budaya hukum kelihatannya masih harus mendapat perhatian khusus dalam studi-studi lanjutan. Memposisikan Pancasila dan Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melihat pada The Original Paradicmatif Values of Indonesian Cultural and Society adalah menjadi dasar dan arah bagi pilihan politik hukum Indonesia ke depan, agar hukum Indonesia yang dilahirkan melalui proses transplantasi dapat menghasilkan kaedah hukum yang think globally, commit nationally dan act locally. Dengan kondisi yang demikian, transplantasi hukum Hak Cipta Indonesia yang berasal dari hukum asing (apakah pada awalnya berasal dari hukum Kolonial Belanda dan terakhir disesuaikan dengan TRIPs Agreement) semuanya bermuara pada kekuatan tarik-menarik secara politis dengan berbagai kekuatan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dinamika sejarah politik hukum pembentukan Undang-undang Hak Cipta Nasional sekalipun tidak terekam dan tidak terdokumentasi secara ilmiah, hasilnya dapat dirasakan dalam babakan sejarah penerapan hukumnya di Republik Indonesia tercinta ini. Menjadi harapan bagi negara ini ke depan menyelaraskan hukum yang dilahirkan itu dengan kepentingan Indonesia tanpa harus menghambat Indonesia untuk turut dalam percaturan (ekonomi dan politik) global dimana hukum sebagai salah satu instrumentnya. Merajut kepentingan hukum nasional dan dipertautkan dengan tuntutan globalisasi (pasca ratifikasi TRIPs Agreement), diharapkan dapat melahirkan konsep hukum hak cipta yang commit nationally, think globally dan act locally. Meninjau kembali, menguak jalannya sejarah transplantasi hukum asing ke Undang-undang Hak Cipta Indonesia, menguak substansi ideologis-filosofisnya, membuka kembali latar belakang politik hukum yang mewarnai gagasan proses transplantasi yang dilakukan ketika undang-undang itu dibuat, menjelaskan berbagai kegagalan yang pernah terjadi dalam penerapannya (law enforcement-nya) guna memperbaiki kegagalankegagalan itu, sehingga semuanya menjadi jelas, terang dan dapat mengantarkan studi ini menjadi model pembangunan hukum Indonesia ke depan jika negeri ini akan menggunakan proses transplantasi hukum asing dalam kebijakan politik hukumnya di kemudian hari, kesemua itu adalah merupakan alasan penting, mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Selain penting artinya bagi melahirkan konsep pembangunan hukum nasional yang sesuai dengan jiwa dan roh filsafati 93 hukum Indonesia dalam arti politis, penelitian ini juga penting artinya bagi pengembangan akademis dan kepentingan praktis pada tataran basic policy, guna menemukan hukum yang sesuai dengan tata nilai dan jati diri bangsa Indonesia yakni Pancasila yang merupakan abstraksi the original paradicmatic value of Indonesian culture and society, sebagai groundnorm tanpa harus mengabaikan posisi dan keberadaan Indonesia ditengah-tengah pergaulan internasional, sehingga pada gilirannya pada tataran anactment policy, pemberlakuan undang-undang ini dapat berterima di hati masyarakat. B. Teori, Konsep dan Metode 1. Teori Disertasi ini berpijak pada lima teori hukum. Teori yang pertama adalah teori negara hukum modern (welfare state) yang dalam disertasi ini kami posisikan sebagai grand theory yang digunakan untuk mengkaji peran negara dalam menciptakan hukum dan penerapannya dalam kehidupan bernegara untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang tertera di dalam konstitusi Negara Republik Indonesia (Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat). Teori yang kedua adalah, teori sosiologi hukum dengan mengacu pada teori Robert B. Seidman (the law of non transferability of law) yang memiliki keterkaitan dengan konsep yang berhubungan dengan transplantasi hukum. Dalam disertasi ini teori ini diposisikan sebagai middle range theory, digunakan untuk mengkaji secara kritis penerapan ketentuan The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) ke dalam Undang-undang Hak Cipta Nasional dan merumuskan konsep politik hukum Hak Cipta Nasional di masa depan dalam rangka melindungi kepentingan nasional. Yang ketiga adalah teori politik hukum dengan menempatkan hukum dalam kerangka sistem nasional yang dikembangkan oleh M. Solly Lubis. Bahwa keberlakuan hukum harus diukur pada skala tingkat keselarasannya dengan sub sistem nasional lainnya dalam satu sistem yang disebutnya sebagai sistem nasional. Teori keempat adalah teori politik hukum dari Hikmahanto Juwana dengan menempatkan hukum pada tataran basic policy, hukum dipandang sebagai instrumen politik dan pada tataran anactment policy hukum diposisikan sebagai komoditas politik. Yang kelima teori nuances yang pertama kali dikemukakan oleh Mahadi yakni mempertemukan kedua sisi hukum yang berbeda dalam proses perjumpaan (interaksi) masing-masing sistem hukum yang didorong 94 oleh tuntutan peradaban. Tiga teori yang disebut terakhir ini dalam disertasi ini digunakan sebagai applied theory. Kelima kerangka dasar teori hukum yang dikemukakan di atas, akan digunakan dalam menganalisis fungsi dan peranan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Hak Cipta dalam proses transplantasi hukum asing sepanjang perjalanan Undang-undang Hak Cipta Indonesia mulai dari Auteruswet 1912 Stb. 600 yang bersumber dari hukum kolonial sampai dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 yang mengacu pada TRIPs Agreement Tahun 1994, dengan uraian sebagai berikut : 1.1. Grand Theory Teori negara hukum yang menjadi grand theory dalam disertasi ini adalah sebuah pilihan yang didasarkan pada sebuah pertimbangan bahwa, penelitian ini berpangkal pada landasan dasar negara Indonesia yang menegaskan dalam konstitusinya bahwa negara ini adalah negara hukum (rechtstaat) bukan negara kekuasaan (machtsstaat). Dengan begitu semua rangkaian pengelolaan manajemen negara harus berlandaskan hukum. 69 69 Prinsip negara hukum secara tersurat dan tersirat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD ’45 yang berbunyi Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi UUD negaralah yang menjadi acuan bekerja lembagalembaga negara. Lihat Jimly Asshiddiqie, (ed) Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indoensia Pasca Reformasi, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hal. 292. Dalam sejarah modern, gagasan Negara Hukum itu sendiri dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum sebagai sistem yang fungsional dan berkeadilan, dengan menata supra dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum perlu dibangun (law making) dan ditegakkan (law enforcing) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang tertinggi. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar, dibentuk pula Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai the guardian dan sekaligus the ultimate interpreter of the constitution. Gagasan, cita atau ide negara hukum, selain terkait dengan konsep rechtsstaat dan rule of law, juga berkaitan dengan nomocracy yang berasal dari kata nomos dan crotos. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan demos dan cretos atau kretion dalam demokrasi. Nomos berarti norma sedangkan crotos adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Namun, prinsip kedaulatan hukum atau the rule of law itu sendiri tidak selalu baik, karena hukum itu sendiri dapat dibuat dan ditetapkan secara semenamena oleh penguasa. Jerman di bawah pemerintahan Hitler juga menganut prinsip rechtsstaat atau negara hukum, tetapi hukum yang diakui berdaulat itu ditetapkan secara sewenang-wenang oleh Hitler sebagai dictator dan “demagog”. Karena itu, berkembang 95 Kelahiran teori negara hukum mengalami perjalanan sejarah yang panjang. Absolutism kekuasaan raja-raja di benua Eropa pada abad 10-17 mendorong rakyat untuk melakukan perlawanan yang puncaknya melahirkan negara konstitusional.70 Ide negara hukum tidak hanya terkait dengan konsep rechtsstaat dan the rule of law, melainkan juga dengan konsep nomocrasy. Konsep yang disebut terakhir ini berkait erat dengan pemikiran kedaulatan hukum atau norma (nomos). Nama-nama seperti : Ibnu Khaldun, Immanuel Kant, Friedrich Julius Stahl dan Albert Venn Dicey adalah sederetan nama-nama yang mengetengahkan tentang gagasan negara hukum. Negara hukum menurut Dicey, harus mencerminkan tiga kriteria dari the rule of law. Menurut Dicey : “…in the first place, the absolute supremacy or predominance of regular law as opposed to the influence of arbitrary power, and excludes the existence of arbitrariness, of prerogative, or even of wide discretionary authority on the part of the government. It means, again, equality before the law, or equal subjection of all classes to the ordinary law of the land administered by the ordinary law courts ; lastly, may be used as a formula for expressing the fact that with us the law of the constitution, the rules which in foreign countries naturally form part of constitutional code, are not the source but the consequence of the rights of individual, as defined and enforced by the courts. 71 Tiga unsur rule of law, menurut Dicey pertama, keharusan adanya supremasi absolute atau keunggulan hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah (penguasa) dan tindakan-tindakan negatif yang mungkin dilakukan oleh pemerintah (penguasa). Kedua, adanya prinsip persamaan dihadapan hukum yang berlaku bagi semua anggota masyarakat, tidak terkecuali orang-orang yang sedang memegang kekuasaan pemerintahan. Ketiga, konstitusi bukanlah sumber terhadap perlindungan hak asasi manusia tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang sudah ada sejak manusia dilahirkan. pula istilah democratic rule of law dalam bahasa Inggris atau democratische rechtsstaat dalam bahasa Belanda. 70 Pergulatan perlawanan rakyat terhadap absolutism kekuasaan raja di Eropa tak kurang dari sepuluh abad. Perlawanan yang dilakukan mulai dari feodalisme kekuasaan raja yang absolute sampai pada pengebirian terhadap hak asasi manusia. 71 A.V. Dicey, Introduction to the Study of the Law the Constitution, Macmillan Press, London, 1971, hal. 202-203. 96 Tujuan negara dirumuskan dalam konstitusi antara lain memajukan kesejahteraan sosial, dengan demikian jika dihubungkan dengan negara hukum Indonesia maka Indonesia adalah negara rechts staat yang welfare staats yang dikategorikan sebagai negara hukum modern. Negara hukum modern yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat (negara kesejahteraan). Produk-produk hukum yang dilahirkan haruslah bermuara pada kesejahteraan rakyat, jika ada produk hukum yang bertentangan dengan konsep negara kesejahteraan, produk hukum semacam itu harus ditolak (mekanismenya dapat melalui hak uji materil). Kerangka teori inilah yang diletakkan sebagai grand theory dalam penulisan disertasi ini. 1.2. Middle Range Theory Dalam upaya untuk mewujudkan negara hukum yang sejahtera, maka semua produk hukum yang dilahirkan harus diarahkan secara substantif pada upaya perwujudan kesejahteraan rakyat. Hukum yang akan dibuat atau yang dicita-citakan (ius constituendum) harus dirumuskan ke arah mensejahterakan rakyat, demikian juga hukum yang diberlakukan saat ini (ius constitutum) harus diuji secara substantif apakah benar-benar berisikan materi hukum yang menjamin untuk terwujudnya masyarakat sejahtera. Hukum yang diproduk itu dapat saja hukum yang bersumber dari legal culture atau berdasarkan living law masyarakat Indonesia sendiri. Akan tetapi tidak sedikit hukum Indonesia seperti yang kami telah sebutkan diawal tulisan ini – yang ada sekarang ini adalah hasil adopsi, hasil konkordansi, hasil resepsi, dengan kebijakan politik hukum negara – adalah hukum yang bersumber dari hukum asing. 72 Pengadopsian ataupun pencangkokan hukum asing, akan terus berlangsung dan ini jika dilakukan tidak dengan penuh perhitungan, akan dapat berujung pada “tergadainya” bangsa dan negara ini kepada bangsa lain. Hukum yang dilahirkan akan menjadi asing bagi rakyatnya, akan bersifat represif, keberlakuannya tertolak dan yang paling fatal hukumnya bisa mengkriminalkan rakyatnya (kriminalisasi 72 Hukum perkawinan bagi umat Islam, hukum waris, hukum zakat yang dikenal menjadi kompilasi hukum Islam adalah bersumber dari hukum Islam yang bukan hukum Indonesia asli. Begitu juga Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Acara Perdata adalah hukum yang diadopsi dari hukum Belanda. Hukum Indonesia yang tersusun dalam kodifikasi parsial seperti UU PT, UU Pasar Modal dan Peraturan Perundang-undangan HKI (Hak Cipta, Merek, Paten dan lainlain) adalah hukum yang bersumber dari berbagai sistem hukum asing (mixed) Belanda, Amerika dan berbagai Konvensi Internasional. 97 hukum). Sebaliknya jika dilakukan dengan penuh kearifan hukum yang dilahirkan itu dapat memacu kreatifitas masyarakat, memacu hukumnya menjadi responsif, keberlakuannya dapat diterima masyarakat pada akhirnya dapat mendorong percepatan untuk perwujudan kesejahteraan rakyat. Robert B. Seidman dalam studinya melahirkan teori yang sangat terkenal tentang pengadopsian atau transplantasi hukum asing ini yakni “Theory The Law of Nontransferability of Law”. Kegagalan sebuah negeri di Afrika (bekas jajahan Inggeris) untuk menerapkan hukum Inggris di bekas negara jajahannya itu segera setelah Inggris meninggalkan Afrika, adalah suatu bukti bahwa transplantasi atau adopsi itu gagal. 73 Tapi tidak jarang pula, transplantasi hukum asing itu memperlihatkan hasil yang baik, walau pada awalnya kurang dapat diterima oleh masyarakatnya. Di Turki dan di beberapa negara bekas koloni Inggeris, seperti Malaysia, Singapura, transplantasi hukum asing itu dipandang cukup berhasil. Teori Seidman ini, kami jadikan sebagai middle range theory dalam disertasi ini. 1.3. Applied Theory Ada tiga teori yang digunakan sebagai applied theory dalam disertasi ini yang pertama adalah theory Politik Hukum dari Hikmahato Juwana, kedua theory politik hukum dari M. Solly Lubis dan ketiga theory nuances dari Mahadi. 73 Lihat Seidman, Ann, Robert B. Seidman, State and Law in The Development Process Problem-Solving and Institutional Change in the Third World, St. Martin’s Press, 1994, hal. 69. Lihat juga Seidman, Robert B., The State, Law and Development, St. Martin's Press, New York, 1978, hal. 125.Indonesia sendiri dalam sejarah pemberlakuan KUH Perdata yang berasal dari Kolonial Belanda juga gagal. KUH Perdata oleh Mahkamah Agung hanya diposisikan sebagai pedoman saja bagi hukum untuk memutus, tapi bukan sebagai hukum formal yang ketat untuk diikuti. Begitupun setelah Buku II KUH Perdata dicabut selalu dibukukan dalam UUPA No. 5 Tahun 1960 tentang Hukum Agraria, dengan mengambil sebagian besar norma hukum KUH Perdata. Lihatlah konsep hak milik (eigendom). Konsep HGU (erfacht), Hak Pakai, Hak Guna Bangunan yang diambil dari BW gagal diimplementasi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Tak ada HGU Asing Sacfindo, Lonsum yang tidak diperpanjang akibatnya hak-hak atas tanah itu tak pernah dapat didistribusikan ke rakyat. HGU sama maknanya dengan hak milik, terkuat, terpenuh dan hilang fungsi sosialnya. Rakyat kehilangan sumber pekerjaan, akhirnya menjadi TKW di negara asing. Demikian juga tentang Hukum Lingkungan, Hukum Perlindungan Konsumen, gagal diterapkan di Indonesia. 98 1.3.1. Teori Politik Hukum dari Hikmahanto Juwana Hikmanto Juwana, memaknai politik hukum yakni berbagai tujuan dan alasan yang menjadi dasar dibentuknya perundangundangan. Tujuan hukum, apakah untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum atau kemanfaatan yang ingin dicapai adalah langkahlangkah politik hukum. Mengapa peraturan perundang-undangan itu dibentuk, mengapa isinya demikian, untuk tujuan apa peraturan perundang-undangan itu dibuat, adalah merupakan politik hukum, demikian Hikmahanto Juwana. 74 Oleh karena itu menurut beliau, politik hukum tidak berhenti pada saat pembuatannya sebagai kebijakan dasar (basic policy) akan tetapi juga pada saat penerapannya sebagai kebijakan pemberlakuan (anactment policy). Terdapat “jembatan” penghubung antara keduanya dan keduanya juga harus ada konsistensi dan korelasi yang erat, agar tercapainya ikhtiar tujuan politik hukum yang telah ditetapkan (turthering policy goals). Dalam tulisannya yang lain Hikmahanto Juwana menyebutkan bahwa hukum adalah sebagai instrumen politik dan jika tidak dimaknai secara tepat dalam skala Internasional dapat berubah menjadi alat intervensi atas kedaulatan negara dalam proses legislasi di Indonesia, karena melalui langkah itu tindakan intervensi politik mendapat justifikasi atau tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum Internasional. 75 Dalam praktek penegakan hukum di Indonesia, Hikmahanto Juwana juga sampai pada satu kesimpulan bahwa penegakan hukum di Indonesia telah menjadi komoditas politik, dalam berbagai intensitasnya. Hal itu disebabkan karena penegakan hukum itu bisa “diatur” jika kekuasaan menghendaki. Aparat penegak hukum didikte oleh kekuasaan bahkan diintervensi dalam penegakan hukum. Lebih lanjut Hikmahanto menegaskan : Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas karena penguasa memerlukan alasan sah untuk melawan kekuatan pro-demokrasi atau pihak-pihak yang membela kepentingan rakyat. Tetapi penegakan hukum akan dibuat lemah oleh 74 Hikmahanto Juwana, Politik Hukum Undang-undang Bidang Ekonomi di Indonesia, Op.Cit, hal. 28. Paling tidak, menurut uraian Hikmahanto Juwana, ada dua hal penting sebagai alasan mengapa diperlukan politik hukum ; pertama, untuk alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan ; kedua untuk menentuan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dalam rumusan pasal-pasal dalam perundang-undangan tersebut. 75 Lebih lanjut lihat Hikmahanto Juwana, Hukum Sebagai Instrumen Politik : Intervensi Atas Kedaulatan Dalam Proses Legislasi di Indonesia, dalam Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Gagasan dan Pemikiran Tentang Pembaharuan Hukum Nasional, Volume III, Jakarta, 2004, hal 55. 99 kekuasaan bila pemerintah atau elit-elit politik yang menjadi pesakitan. Penegakan hukum sebagai komoditas politik ini menjadi sumber tidak dipercayanya penegakan hukum di Indonesia. ……. Problem lain dari lemahnya penegakan hukum adalah penegakan hukum yang dilakukan secara diskriminatif. Tersangka yang mempunyai status sosial yang tinggi di tengah-tengah masyarakat akan diperlakukan secara istimewa. Penegakan hukum seolah-olah hanya berpihak pada si kaya tapi tidak pada si miskin. Bahkan hukum berpihak pada mereka yang memiliki jabatan dan koneksi dari para pejabat hukum atau akses terhadap keadilan. 76 Demikian juga dalam tataran basic policy hukum dapat menjadi alat intervensi negara maju terhadap negara berkembang. Hal ini sesuai dengan fungsi hukum dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Selain sebagai alat pengubah dan alat kontrol masyarakat, hukum juga dapat berfungsi sebagai instrumen politik. Sebagai instrumen politik, hukum dapat digunakan untuk mencapai tujuantujuan tertentu. Dalam uraiannya Hikmahanto Juwana menegaskan bahwa : Keikutsertaan suatu negara dalam perjanjian internasional berarti negara tersebut dengan sengaja membebankan dirinya melaksanakan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam perjanjian internasional. Salah satu kewajiban tersebut adalah transformasikan ketentuan yang ada dalam perjanjian internasional dalam hukum nasionalnya. Ini berlaku pula bagi Indonesia. Keikutsertaan Indonesia dalam berbagai perjanjian internasional akan menimbulkan kewajiban bagi Indonesia untuk melakukan sejumlah amandemen terhadap peraturan perundang-undangannya. Bila ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan maka harus diselaraskan dengan perjanjian internasional yang diikuti. Sebagai contoh dibidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sejak tahun 2000 hingga 2002, sebagai kewajian keikutsertaan Indonesia dalam Trade-Related aspects of Intellectual Property rights (TRIPs), pemerintah telah 76 Hikmahanto Juwana, Penegakan Hukum Dalam Kajian Law and Development : Problem dan Fundamen Bagi Solusi di Indoensia, Pidato Ilmiah, Disampaikan pada Acara Dies Natalis Ke-56 Universitas Indonesia, Kampus UI Depok, 4 Februari 2006, hal.16. 100 mengamandemen UU Paten, UU Merek, UU Hak Cipta, bahkan mengintrodusir UU Rahasia Dagang, UU Desain Industri dan UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. 77 Dengan bertolak dari pendekatan sejarah Pasca Perang Dunia II bahwa proses dekolonisasi telah menyebabkan munculnya banyak negara baru dan diikuti dengan pertarungan bisnis dengan sistem pasar bebas yang terbuka, Hikmahanto sampai pada puncak pemikirannya bahwa, pada tataran basic policy, hukum adalah merupakan instrumen politik dan pada tataran anactment policy penegakan hukum sebagai komoditas politik. Pandangan inilah yang kemudian dijadikan sebagai kerangka teori dalam penelitian ini. 1.3.2. Teori Sisnas M. Solly Lubis Harold J. Laski, menegaskan kebijakan dasar negara yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan adalah merupakan politik hukum. 78 Isi hukum (meminjam istilah Lawrence Friedman, substansi hukum) yang dibentuk oleh lembaga legislatif adalah sesungguhnya hasil dari politik hukum. Kemana hukum itu diarahkan, demikian Padmo Wahyono berpendapat, adalah merupakan politik hukum. 79 Untuk itulah hukum harus dilihat keberadaannya dalam satu sistem. Hukum tak dapat dilihat secara parsial dalam sistem sosial atau sistem nasional. Pandangan terakhir ini, dikembangkan oleh M. Solly Lubis dalam aktivitas perkuliahan di Universitas Sumatera Utara dan difahami sebagai teori politik hukum sebagai teori sisnas. Hukum yang dilahirkan dan diterapkan tidak boleh keluar dari kerangka sistem nasional, tidak boleh keluar dari jati diri bangsa, tidak boleh keluar dari landasan ideologis-filosofis bangsa dan negara dan sudah semestinya semua produk hukum yang lahir mengacu pada the original paradicmatic value of Indonesian culture and society. Karena itulah hukum dalam teori M. Solly Lubis harus ditempat sebagai bahagian dari sub sistem politik dalam sistem nasional. Menurut beliau, semua 77 Lebih lanjut lihat Hikmahanto Juwana, Hukum Sebagai Instrumen Politik : Intervensi Atas Kedaulatan Dalam Proses Legislasi di Indonesia, Op.Cit, hal 58-59. 78 Harold J. Laski, Studies in Law and Politics, Transaction Publisher, London, 2010, hal.125. 79 Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 160. 101 hukum, apakah pada waktu pembuatannya (basic policy), maupun pada waktu penerapannya (anactment policy) dipengaruhi oleh faktor non hukum (sebagai sub sistem) dalam sistem nasional. Hukum adalah produk politik. Hasil dari kekuatan politik, demikian uraian M. Solly Lubis. 80 Secara sederhana M. Solly Lubis menggambarkan tentang kedudukan hukum sebagai sub sistem dalam sistem politik Indonesia dalam skema berikut : 80 Materi kuliah M. Solly Lubis, selama kurun waktu semester Ganjil pada Program Pendidikan S3 Ilmu Hukum TA 2011-2012. 102 103 Politik hukum sesungguhnya adalah keseluruhan proses tentang hukum, baik pada waktu pembuatannya maupun pada waktu penerapannya. Bahkan ketika hukum itu diterapkan dievaluasi capaiancapaiannya, yang dapat dijadikan umpan balik bagi penyempurnaan kembali norma hukum itu untuk masa-masa yang akan datang. Ditemukan strateginya, apakah itu strategi dalam merumuskan norma hukum (basic policy) baru atau strategi penerapannya (anactment policy). Sebagai hasil dari kekuatan politik, maka hukum berisikan kemauan politik penguasa. Kerangka teori inilah sebagai teori terapan kedua yang digunakan sebagai pisau analisis dalam disertasi ini. Mengapa peraturan perundang-undangan Hak Cipta Nasional (basic policy) dalam pasal-pasalnya berbunyi demikian ? Jika ditempatkan dalam kerangka sistem nasional, menurut teori sisnas M. Solly Lubis, pada saat Undang-undang Hak Cipta itu dibuat (basic policy) suasana internal dan eksternal apa yang sedang dihadapi Indonesia ? Suasana itu diuji berdasarkan faktor ideologi, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Efek-efek konstruktif dan destruktif apa yang kemudian muncul setelah kebijakan (policy) itu diambil. Pada tataran penerapannya (anactment policy), akan dapat diuji dengan teori sisnas ini, tingkat kualitas ketahanan nasional Republik Indonesia dengan mengukur efektifitas penegakan Undang-undang Hak Cipta Nasional dengan mengambil kasus perlindungan karya sinematografi. Uraian di atas, jika dihubungkan dengan skema hasil olah pikir M. Solly Lubis dalam bukunya “Manajemen Strategis Pembangunan Hukum” 81 semakin menguatkan teori sisnas yang beliau perkenalkan. Skemanya sebagai berikut : 81 M. Solly Lubis, Manajemen Strategis Pembangunan Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 127. Bandingkan dengan pendapat Moh. Mahfud MD, bahwa politik hukum adalah sebagai keseluruhan proses pembuatan dan pelaksanaan hukum, ke arah mana hukum akan dibangun atau ditegakkan, Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2009 , hal. 54. 104 105 Skema di atas menggambarkan tentang keharusan untuk menempatkan Sistem Pembangunan Hukum Nasional (Sisbangkumnas) dalam kerangka sistem nasional, dengan mengacu pada kerangka kebijakan politis yang mempergunakan pendekatan sistem berdasarkan pandangan konseptual strategis. Setelah ditemukan tingkat efektivitas penerapan Undangundang Hak Cipta Nasional, maka hasil temuan itu menjadi umpan balik bagi penyusunan konsep (politik hukum) Undang-undang Hak Cipta Nasional yang baru dengan mempertimbangkan seluruh aspek non hukum yang mengitari kebijakan (policy) itu dengan menempatkannya dalam sistem nasional. Politik hukum seperti apa yang harus ditempuh dan dikembangkan ke depan inilah yang dirumuskan sebagai something new. Siklus ini akan terus bergerak melingkar selama negeri ini terbentang dan hukum yang dilahirkan tidak keluar dari “rel” kerangka sistem nasional. Inilah pemaknaan yang dalam dari teori Sisnas M. Solly Lubis yang digunakan sebagai pisau analisis dalam disertasi ini. Selanjutnya guna mempertajam analisis ke-sistem-an berdasarkan teori Sisnas ini, diturunkan satu lagi bagan (skema) korelasi antara teoritisi dan praktisi dalam upaya pembinaan hukum sebagai berikut : 106 107 Menurut pandangan M. Solly Lubis, diperlukan kerjasama antara kalangan teoretisi dengan kalangan praktisi. Hal ini dimaksudkan untuk menjembatani konsep teori yang dituangkan di atas kertas dengan pengalaman empiris kalangan praktisi ketika peraturan perundang-undangan itu diterapkan di lapangan. Pandangan-pandangan teoretis dan pengalaman praktis kesemuanya bermuara pada melahirkan konsep pemikiran baru yang dapat disumbangkan guna pembinaan hukum nasional kepada institusi negara (prolegnas dan relegnas) yang melakukan aktivitas persiapan penyusunan undang-undang yang dirumuskan sebagai politik hukum (legal policy). Hasil capaian institusi legislasi nasional ini melahirkan peraturan perundang-undangan yang kemudian diterapkan (diberlakukan) di tengah-tengah masyarakat. Pelaksanaannya kemudian dipantau dan dinilai (monitoring) kembali oleh kalangan teoretisi (akademis) setelah mendengar pengalaman empirik dari kalangan praktisi. Hasil monitoring ini di kemudian hari kembali dijadikan umpan balik (feedback) untuk melahirkan kebijakan politik hukum yang baru lagi. 1.3.3. Teori Nuances Mahadi Mahadi mengawali uraian teori nuances dengan mengatakan, manusia adalah makhluk sosial (human being). Hubungan manusia dengan manusia agar kepentingan tidak saling bertubrukan, harus diatur oleh hukum. Mulanya bisa berupa norma-norma kebiasaan, norma agama, adat istiadat dan lain sebagainya. Kemudian meningkat menjadi norma hukum. Tiap-tiap manusia mungkin mempunyai kebiasaan, adat istiadat, norma agama dan norma hukum. Bahkan norma hukumnya sendiri berbeda dengan norma hukum yang digunakan orang lain, berbeda dari bangsa lain, karena berbeda sistem hukumnya. Akan tetapi karena ada hubungan, ada relasi antara kelompok masyarakat yang satu dengan masyarakat lain yang berbeda pada norma hukum yang dianutnya, berbeda sistem hukumnya, maka kemungkinan akan terjadi ketidak sesuaian. Mungkin akan terjadi perbenturan. Perbenturan itu bila dibiarkan dapat menimbulkan stagnasi. Terhenti pada satu titik buntu. Kebuntuan itu tidak boleh dibiarkan. Tidak boleh didiamkan. Jalan buntu itu harus dibuka, harus ditetas satu demi satu. Mulai dari celah kecil sampai ada ruang besar untuk dapat dimasuki dan ditemukan jalan baru guna penyelesaiannya. Dicarikan titik temunya. Dibuang titik-titik perbedaan, dicari titik-titik persamaan. Ditemukan nuansanya (nuances). Nuansa bermakna suatu titik temu yang samarsamar akan perbedaan dan samar-samar akan persamaan. Tidak benar- 108 benar berbeda dan tidak benar-benar sama. Kedua kutub yang berbeda, masing-masing bergerak, kemudian bertemu ditengah. Titik tengah itulah yang oleh Mahadi disebutnya sebagai “Nuances”.82 Teori Mahadi ini mirip dengan teori harmonisasi hukum. Jika digambarkan dalam bentuk garis grafis, teori nuances dari Mahadi ini dapat dilukiskan dalam skema sebagai berikut : Skema 6 Teori Nuances Mahadi A1 A C A2 B1 B2 A3 B B3 Nuances A = Sistem hukum A (Varian A1, A2, A3) B = Sistem hukum B (Varian B1, B2, B3) C = Nuances (pertemuan berbagai sistem hukum) Alur pemikiran teori yang kami gunakan dalam disertasi ini dapat kami tuangkan dalam skema sebagai berikut : 82 Mahadi, Falsafah Hukum Suatu Pengantar, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hal. 24. Lihat juga Mahadi, Suatu Perbandingan Antara Penelitian Masa Lampau Dengan Sistem Metode Penelitian Dewasa Ini Dalam Menemukan Asas-Asas Hukum, Makalah, Kuliah pada Pembinaan Tenaga Peneliti Hukum, BPHN, Jakarta, 1980, hal. 52. 109 110 2. Konsep Konsep dimaknai sebagai, definisi khusus yang diberikan atas sesuatu yang diintegrasikan melalui proses abstraksi yakni menghilangkan atau memisahkan aspek realitas tertentu dari unit-unit mental yang beragam kemudian menjadi entitas mental baru yang dipakai sebagai unit tunggal pemikiran. 83 Istilah transplantasi atau pencangkokan yang digunakan dalam disertasi ini adalah istilah yang lazim digunakan dalam ilmu kedokteran atau pertanian. Istilah transplantasi jantung, pencangkokan tanaman durian atau rambutan adalah istilah yang kerap kali kita jumpai dalam literatur ilmu kedokteran dan pertanian. Konsep transplantasi hukum sebenarnya tidak jauh berbeda pemaknaannya dengan transplantasi jantung atau pencangkokan rambutan, yaitu mengambil jantung dari tubuh seseorang (dari luar) untuk dipasangkan pada tubuh orang lain yang memerlukan jantung tersebut. Tingkat keperluannya sesuai analisis dan diagnosis dokter menurut ilmu kedokteran. Begitulah konsep transplantasi hukum ini jika dihubungkan dengan obyek studi ilmu hukum. Konsep transplantasi hukum dimaknai sebagai kebijakan suatu negara untuk mengambil hukum asing yang berasal dari negara lain untuk dijadikan sebagai hukum di negara sendiri. Sama halnya dengan pencangkokan jantung, tubuhnya sudah ada, maka dalam transplantasi hukum, struktur dan kulturnya sudah ada, substansi hukumnya yang akan dicangkokkan. Transplantasi dilakukan dengan berbagai cara ; dengan sadar atau tanpa disadari, bergulir dalam jarum jam sejarah yang panjang pada kasus transplantasi Undang-undang Hak Cipta diawali dari Auteurswet 1912 sampai dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2002, 83 Terminologi konsep berasal dari bahasa Inggris “concept”. Istilah konsep dapat diurutkan dari bahasa Latin “conceptus” dari akar kata “consipere” yang berarti memahami, menerima, menangkap, merupakan gabungan dari kata “con” artinya bersama dan “capere” artinya menangkap atau menjinakkan. Oleh karena itu kata “konsep” memiliki banyak makna. Akan tetapi secara umum dapat difahami bahwa konsep adalah pemaknaan yang dirumuskan secara abstrak atas suatu fenomena yang mewakili dari entitas-entitas tertentu yang kemudian menjadi pemahaman yang dapat diterima secara universal. Dalam terminologi ilmu hukum, konsep tentang “mati” berbeda dengan konsep “mati” menurut terminologi ilmu kedokteran. Concept an idea or a principle that is connected with sth abstract, the concept of social class, concepts such as civilization and government. He cant grosp the basic, concepts of mathematics the concept that everyone should have equality of opportunity. Lebih lanjut lihat A.S. Hornby, Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, University Press Oxford, New York, 2000, hal. 265. Lihat juga Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hal. 387. 111 undang-undang disebut terakhir ini disusun merujuk pada persetujuan TRIPs 1994. Dalam konteks tranplantasi hukum Internasional ke dalam hukum nasional, konsep transplantasi dimaknai sama dengan konsep transformasi hukum Internasional ke dalam hukum nasional khususnya dalam perjanjian internasional yang termasuk dalam katagori law making, yakni keharusan suatu negara untuk menterjemahkan ke dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya, terhadap perjanjian Interrnasional yang telah diikutinya. Keharusannya semacam ini akan membawa dampak terhadap penyusunan Undang-undang Hak Cipta Nasional. Dampak yang sangat mendasar adalah terjadi pergeseran nilai-nilai ideologis-filosofis Pancasila sebagai grundnorm, nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia yang merupakan the original paradicmatic values of Indonesian cultural and society yang di dalamnya memuat tata nilai atau sekumpulan asas-asas hukum. Konsep tentang pergeseran nilai, dimaknai sebagai bergesernya pilihan-pilihan tata nilai dalam penyusuan norma hukum hak cipta nasional yang semula bertolak dari ideologi-filosofis Pancasila sebagai grundnorm, akan tetapi dalam proses legislasi berujung pada norma konkrit yang tercerabut dari landasan ideologis-filosofis Pancasila dan lepas dari sosio-kultural masyarakat Indonesia. Bergeser dari nilai ideologi Pancasila ke nilai ideologi liberal-kapitalis. Bergeser dari nilai sosial-kultural masyarakat Indonesia ke nilai-nilai masyarakat Barat. Bergeser dari nilai komunal ke nilai individualis dan seterusnya. Bergeser dalam arti meninggalkan nilai-nilai yang sudah lama dianut atau nilai yang seharusnya dianut digantikan nilai baru, jadi dibedakan dengan perubahan. Kalau perubahan, langkah-langkah perubahan itu bertolak dari nilai lama atau nilai yang ada, secara perlahan-lahan mengadopsi nilai yang baru tanpa mengenyampingkan nilai yang lama. Oleh karena terjadi pergeseran-pergeseran nilai seperti diuraikan di atas, ketika Undang-undang Hak Cipta itu diterapkan terjadi penolakan, baik penolakan secara aktif maupun pasif. Kesemua itu berujung pada tingkat efektivitas penegakan hukum yang lemah. Konsep efektivitas penegakan hukum dimaknai sebagai tingkatan tinggi rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat dapat diukur dari tingkat pengetahuan masyarakat terhadap norma hukum itu sendiri dan tingkat kepatuhannya terhadap norma hukum itu, sedangkan tingkat kepatuhan hukum dapat diukur dari tingkat keberterimaan dan penolakan masyarakat terhadap norma hukum itu. 112 Pilihan terhadap transplantasi hukum sebagai pilihan politik negara dalam penyusunan hukum nasional, bukanlah pilihan yang bebas. Pilihan itu didasari pada pengaruh eksternal dan internal. Secara eksternal pengaruh globalisasi telah membawa dampak pada pilihan politik hukum. Hukum yang telah selesai untuk dioperasionalkan, juga membawa dampak terhadap masyarakat sebagai pihak yang terkena dari pemberlakuan norma hukum itu. Perlindungan hak cipta karya sinematografi misalnya, tidak hanya dilindungi di Indonesia atau dibatasi pada tempat hak cipta itu dilahirkan, akan tetapi di seluruh jagat raya. Konsep hukum asing dalam disertasi ini tidak merujuk pada pendefinisian menurut hukum perdata internasional ataupun hukum internasional publik. Hukum asing yang dimaksudkan dalam disertasi ini adalah hukum yang bersumber dari kebudayaan asing, peradaban asing, dasar filosofis dan ideologi asing, sebaliknya yang dimaksud dengan hukum nasional adalah hukum yang dalam proses pembuatannya bersumber dari kebudayaan nasional, peradaban masyarakat Indonesia, dasar filosofis dan ideologi Negara Republik Indonesia atau dalam istilah lain adalah hukum yang bersumber dari the original paradigmatic values of Indonesian culture and society. 3. Metode 1. Pendekatan Sulit untuk mengatakan bahwa hukum itu hanya merupakan gejala normatif yang hanya dapat dilihat dari satu sudut pandang saja,yakni sudut pandang juridis. Jika hukum hanya dipandang sebagai gejala nromatif saja, maka akan terjadi kesulitan untuk merangkum keaneka ragaman yang ada dalam berbagai bidang kajian hukum. Di samping itu juga akan memperkuat kecenderungan konservatif atau menuju pada mitos pendewaan ilmu hukum normatif yang pada gilirannya akan menolak kajian sosiologi hukum, politik hukum, antropologi hukum, sejarah hukum bahkan filsafat hukum. Pada hal untuk melihat realitas sosial hukum yang sesungguhnya haruslah melihat hukum dari berbagai-bagai segi. Hukum menjadi ilmu yang multi paradigma. Deangn cara pandang demikian hukum tidak dilihat sebagai sebuah kebetulan yang dituangkan dalam kitab undang-undang, tetapi sebuah pilihan yang secara sadar dilakukan oleh masyarakat untuk mengatur hubungan kemasyarakatan dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu jika hendak melihat atau mengkaji hukum secara 113 mendalam (kedalaman substansi bukan keluasan) mau tidak mau kajian yang harus dilakukan mestilah menggunakan multi paradigma. 84 Jika hukum dilihat sebagai sekumpulan norma dan asas, maka paradigma yang dipakai adalah paradigma normatif, namun apabila hukum hendak dilihat sebagai sekumpulan perilaku, resultan dari kekuatan politik, kristalisasi dari nilai-nilai budaya, penerapannya dipengaruhi oleh faktor sosiologis dan kultural, keberlakuannya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pilihan kesadaran hukumnya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, maka paradigma kajian yang dipakai adalah paradigma sosiologis. Di sisi lain jika studinya menghendaki kajian masa lampau guna merumuskan masa depan maka pilihan metode kajian sejarah menjadi sesuatu yang tak terelakkan. Begitu juga kalau kemudian kajiannya melihat bagaimana sistem hukum yang sama diterapkan di negara-negara yang berbeda waktu dan tempatnya, yang kemudian melahirkan ”nuansa hukum” yang berbeda, maka metode perbandingan menjadi pilihan yang tepat. Dengan begitu, tidak ada dominasi tunggal dalam pilihan metode dalam penelitian hukum. Pilihan metode tunggal dalam penelitian hukum, tidak akan mampu memecahkan masalah hukum yang multi paradigma itu. Oleh karena itu keluar dari tradisi yang selama ini telah mendominasi model pilihan metode dalam kajian ilmu hukum, maka dalam penelitian ini, pilihan metode yang dilakukan adalah, metode campuran (mixed methods) yang sebenarnya telah diperkenalkan sejak lama oleh para pakar di bidang penelitian. Pilihan metode ini untuk menghilangkan dikotomi antara penelitian kuantitatif dan kualitatif, untuk menghilangkan dikotomi antara penelitian juridis normatif dengan sosiologi empiris dan seterusnya. Pilihan kuantitatif dapat digunakan untuk memverifikasi norma, asas hukum dan doktrin hukum, sedangkan pilihan kualitatif dapat digunakan untuk menciptakan norma, asas hukum dan melahirkan teori baru. Demikian pula pilihan terhadap metode juridis normatif, dapat digunakan untuk memverifikasi norma hukum, asas hukum dan doktrin hukum, dan hasilnya hanya memverifikasi teori hukum, sedangkan pilihan terhadap metode sosiologis dapat digunakan untuk memverifikasi perilaku hukum. Jika keduanya digabungkan dengan memberikan defenisi menurut metode 84 Catatan Kuliah Solly Loebis, Soetandyo Wignyosoebroto, Lili Rasyidi, Herman Rajagukguk dan Tan Kamello, Semester Genap Tahun Ajaran 2010/2011 Program Studi S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum USU 114 campuran tidak hanya menampilkan verifikasi norma, asas dan teori, tapi dapat melahirkan teori baru. Judul penelitian ini menghendaki adanya studi sejarah 85 dengan dicantumkannya kata ”Dari Auteurswet 1912 ke TRIPs Agreement 1994. Studi sejarah hukum menjadi satu bahagian saja dalam pendekatan ini, hal ini untuk menghindarkan disertasi ini dari potensi untuk menjadi kajian sejarah hukum. Penggunaan metodologi sejarah dimaksudkan untuk melihat perjalanan Undang-undang Hak Cipta Indonesia, yang semula berpangkal pada hukum kolonial (Auteurswet 1912 Stb. 600) dan berakhir pada TRIPs Agreement 1994. Sisi sejarah yang akan dilihat adalah aspek kebijakan/politik legislasi yang bersumber pada hukum asing atau transplantasi hukum asing ke hukum nasional. Di balik peristiwa pilihan politik hukum pembentukan undang-undang hak cipta nasional, pasti ada hal-hal yang tak terungkap, jika hanya dilihat dari redaksi norma hukumnya. Akan tetapi tiap-tiap peristiwa pasti ada yang melatar belakanginya. Serupa dengan turunnya ayat-ayat Al-Qur’an yang memiliki asbabun nuzul, maka studi sejarah hukum dalam penelitian tak pelak lagi adalah untuk mengungkapkan “asbabun nuzul” pada tiap-tiap priode perubahan undang-undang hak cipta nasional. Penelitian ini tidak hendak menyalahkan pilihan politik hukum ( yang juga berjalan secara simetris dengan pilihan politik politik ekonomi dan politik kebudayaan ) yang pernah dilakukan oleh negeri ini pada masa lalu , melainkan hendak mencari akar/filosofis/ideologis yang mendasari politik hukum yang dijalankan secara sedemikian dalam kurun waktu antara Auteurswet 1912 sampai pada Undang-undang No. 19 Tahun 2002. Ketepatan dalam merumuskan kebijakan hukum terhadap subyek yang bertanggungjawab merumuskan (pemerintah dan 85 Metode penelitian sejarah dapat digunakan untuk melihat sejarah perkembangan hukum di satu negara seperti yang dilakukan oleh Soetandyo Wignosoebroto dalam tulisannya Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional. Dengan studi sejarah ini kita dapat melihat perjalanan masa lalu arus gerak perkembangan hukum Indonesia dalam lintasan sejarah untuk melihat sisi-sisi lemah dari substansi dan penerapan hukumnya untuk kemudian dijadikan refleksi guna membangun hukum masa depan. Lihat lebih lanjut John Gilissen dan Frits Gorgle, Sejarah Hukum Suatu Pengantar, (Terjemahan Drs. Freddy Tengker, SH, CN), PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hal.124, Lihat juga Soerjono Soekanto, Pengantar Sejarah Hukum, Alumni, Bandung, 1979. Bagaimana pendekatan sejarah digunakan lihat lebih lanjut Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hal. 12. Lihat juga Rifyal Ka’bah, Indonesian Legal History, Program Pascasarjana FH-UI, Jakarta, 2001, hal. 54. Karena bagaimanapun juga hukum adalah kristalisasi dari peradaban umat manusia yang bergulir dalam lintasan sejarah. 115 legislatif) dan menjalankannya (pemerintah dan judikatif), juga menjadi issue penting yang hendak ”disemai” dalam penelitian ini. Apakah ”panennya” menghasilkan bulir padi jernih atau hampa, disinilah diskusi pergulatan pemikiran akan diurai, tentu saja didasarkan pada data sejarah dan informasi yang akurat. Harapan akhir adalah, anak negeri ini dapat menyebar benih padi baru dan menuai hasil panen yang lebih baik. Sejarah yang menguak kebijakan politik hukum yang keliru, belum terbuka lebar, sedikit sekali orang yang menguaknya. Adalah Sudikno Mertokusumo, dari aspek lembaga peradilan (struktur) dan Soetandyo Wignjosoebroto dari aspek substantif. Selebihnya, apakah studi sejarah hukum tidak menarik, atau para ilmuwan dan calon ilmuwan hukum telah terkoptasi dalam pilihan metodologi penelitian hukum normatif, memang menjadi pertanyaan tersendiri. Bagaimanapun juga, studi terhadap hukum harus dibebaskan dari prasangka pro dan kontra terhadap masing-masing pilihan metode penelitiannya. Jika hendak sampai pada ke dalam akar pohon, dengan cangkul saja mungkin tak cukup, perlu tembilang atau walang kekek (beko), untuk menggalinya dengan memadukan pola-pola pendekatan tradisional dan modern. Pilihan metodologi tertentu memang tidak bisa tidak, akan mengundang pendekatan baru, dan tak jarang pula mengundang perdebatan, mungkin tentang cara mencari data atau tentang penafsirannya, tapi apapun yang akan dihasilkan nantinya, harapan akhir dari studi ini adalah, agar dapat sesuatu yang baru, landasan teori baru atau perdebatan baru mengenai bagian terpenting dari perjalanan sejarah pembangunan hukum di negeri ini. Tentu saja ini bukanlah pekerjaan yang mudah, yakni untuk menarik generalisai terhadap semua produk hukum nasional yang meggunakan pilihan politik hukum trasplatasi dengan hanya meneliti pada perjalanan Undang-undang Hak Cipta Nasional. Akan tetapi dengan dipadukan dengan studi normatif yang berujung pada pengabstraksian nilai-nilai yang bersumber dari norma-norma hukum hak cipta nasional yang ditranplantasikan dari norma hukum asing (Auteurswet stb.1912 No.600) lalu kemudian diuji dalam praktek penegakan hukumnya (lawenforcement-nya) melalui data empirik, akan ditemukan prilaku-prilaku politik penyelenggara negara, prilaku lembaga pembentuk undang-undang dan prilaku aparat penegak hukum serta prilaku masyarakat yang pada gilirannya diharapkan dapat ditarik generalisasi. Transplantasi hukum asing ke hukum nasional sarat dengan nuansa politik, ekonomis, sosiologis dan kultural. Situasi ini akan membawa tulisan ini pada pilihan metode campuran yang dikenal 116 dalam ilmu sosial.86 Dengan demikian di samping menempatkan undang-undang hak cipta nasional sebagai fenomena normatif dalam kajian ini undang-undang hak cipta nasional juga ditemaptkan sebgai fenomena sosio-kultural. Hukum selalu diartikan sebagai produk akhir dan kristalisasi kebudayaan. Ada juga yang mengartikannya sebagai produk politik, hasil (resultant) dari kekuatan politik. Sebagai hasil kebudayaan, sebagai produk politik, sebagai fenomena sosial, mau tidak mau untuk melihat secara utuh dan bahkan sebagai fenomena normatif, realiti sosio-kultural hukum, studi ini harus meminjam metode penelitian dari ilmu-ilmu sosial sebagai metode penjelajahan semua fenomena itu dan dipadukan dengan metode penelitian hukum yang murni, yakni metode penelitian hukum normatif. Metode yang menggunakan pendekatan ilmu sosial oleh Jones disebutnya sebagai pendekatan non doktrinal riset, sedangkan metode yang murni yang lazim dipakai dalam ilmu hukum adalah pendekatan doktrinal riset. Keduanya akan dipadukan, namun keluarannya, adalah hukum. 87 Oleh karena itu langkah untuk menjawab teka-teki itu disusun tahap demi tahap. Mulai dari tahap inventarisir norma hukum sampai pada tahap penerapannya. Di antara keduanya (tahap inventarisir dan penerapannya) dijelaskan pula proses pembuatannya (legislasinya, dengan pendekatan politik hukum) dengan disana-sini melihat pada perjalanan sejarahnya (metode sejarah) dan membandingkannya pada kurun waktu yang berbeda dan melihat pula diberbagai negara lain secara sekilas untuk memperkaya khazanah penelitian dengan menggunakan metode perbandingan hukum. Dengan demikian fenomena transplantasi hukum hak cipta dapat tersingkap, ketimpangan 86 Lihat lebih lanjut Abbas Tashakkori, Charles Teddlie, Hand Book Of Mixed Methods In Social & Behavioral Research, (Terjemahan Daryatno), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 25. 87 Mengenai hal ini, lebih lanjut dapat dilihat dari uraian-uraian Lili Rasyidi dalam bukunya Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 55. Hal yang sama juga dapat dilihat dalam uraian Soetandyo Wignjosoebroto Penelitian Hukum Normatif : Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 65, demikian juga uraian-uraian Lili Rasyidi, Soetandyo dan M. Solly Lubis dalam kuliahnya di Program Pasca Sarjana USU sepanjang semester B Tahun 2010 -2011. Pemaduan antara berbagai metode penelitian ini, tidak bisa tidak harus dilakukan. Alasannya adalah : 1. Hukum sarat dengan kompleksitas kehidupan sosial, karena itu tidak bisa dijelaskan dari satu paradigma metodologis saja, butuh beragam perspektif. 2. Hukum memiliki multi paradigma, oleh karena itu pilihan terhadap metode campuran itu akan memperluas cakupan dimensi hukum yang multi paradigma itu untuk mendapat gambaran yang utuh dari realitas sosial hukum yang penuh teka-teki (the full social redity of legal fenomena). 117 dapat terpecahkan, konsep terpahami dan hubungan timbal balik antara berbagai faktor yang mempengaruhi hukum sebagai sub sistem dalam sistem nasional dapat terjalin. Semua penggalan-penggalan informasi apakah itu diperoleh dari data sekunder atau data primer dapat dijalin jadi satu. Dengan langkah-langkah ini semuanya bermuara pada pengembangan teori atau penemuan teori baru sebagai the something new. 88 Mengacu pada uraian di atas, maka dalam penelitian ini dipadukan dua model penelitian hukum yakni : a. Metode penelitian doktrinal riset atau dogmatik. b. Metode penelitian nondoktrinal riset.89 Untuk pendekatan pertama Soerjono Soekanto 90 menggunakan istilah penelitian juridis normatif, sedangkan untuk pendekatan kedua digunakannya istilah sosiologis-empiris. 2. Metode Penelitian Doktrinal Riset Salah satu dari capaian metode penelitian doktrinal riset adalah untuk mencari atau menemukan asas hukum atau doktrin hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Hak Cipta, baik itu peraturan Perundangundangan Nasional (Undang-undang No. 19 Tahun 2002) maupun Perundang-undangan yang bersumber dari hukum asing (The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Bern Convention, Rome Convention).91 Metode ini diawali dari pekerjaan menginventarisir berbagai-bagai peraturan perundang88 Lihat lebih lanjut Abbas Tashakkori, Charles Teddlie, Hand Book Of Mixed Methods In Social & Behavioral Research, (Terjemahan Daryatno), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 54. Memang untuk pilihan metode campuran ini perlu kehatihatian sebab jika keliru bisa menjadi ancaman serius terhadap validitas, karena asumsiasumsi, metodologisnya dilanggar. Namun berapapun tingkat kesulitannya kami memberanikan diri untuk melakukan pilihan metodologis campuran ini, dengan alasan bahwa fenomena hukum memang menghendaki pola pendekatan yang demikian. 89 Soetandyo Wignjosoebroto, Makalah pada Penataran Lanjutan Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Kajian Hukum, Cibogo, 15-16 Oktober 1993. Lihat juga Soetandyo Wignjosoebroto, Metode Penelitian, Bahan Kuliah Bagi Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Tahun 2009/2010 ; Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, ELSAM & HUMA, Jakarta, 2002, hal. 164. 90 Soerjono Soekanto, Identifikasi Hukum Positif Tidak Tertulis Melalui Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, IND-HILL-Co, Jakarta, 1988, hal. 47. 91 Yakni berupa peraturan perundang-undangan yang bersumber dari hukum kolonial dalam hal ini Auteurswet 1912 No. 600 dan Konvensi Internasional seperti Bern Convention, Rome Convention dan TRIPs Agreement. 118 undangan terkait kemudian dilanjutkan dengan pengujian norma per norma. Pada zamannya, mengapa norma itu berbunyi demikian ? Suasana seperti apa yang berlangsung pada saat norma itu disusun. Konvensi Internasional apa yang berlaku pada saat itu dan bagaimana penyesuaiannya dengan hukum Indonesia. Misalnya Konvensi Bern diselaraskan dengan Auteurswet 1912 Stb. No. 600, dan Undangundang Hak Cipta No.6 Tahun 1982, karena ketiganya memiliki hubungan yang kuat dalam proses pembentukannya. Undang-undang Hak Cipta No.12 Tahun 1997 dan Undang-uyndang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, diselaraskan dengan TRIPs Agreement 1994, alasannya juga sama, yakni pembentukan dua undang-undang hak cipta Nasional yang disebutkan terakhir memiliki pertalian atau benang merah dengan TRIPs Agreement. Pengujian dilangsungkan dengan mengukur tingkat keselarasan normatif Undang-undang No. 19 Tahun 2002 dengan ideologi negara (sebagai landasan filosofis penyusunan peraturan perundang-undangan). Pengujian dilanjutkan juga dengan mengkaji ideologi yang tersembunyi dibalik norma-norma Bern Convention, Rome Convention 1961 dan The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) Agreement 1994. Inventarisirpasal-pasal yang terkait dalam proses transplantasi itu dibandingkan satu persatu dalam pasal-pasal undang-undang hak cipta nasional. Kemudian diikuti dengan klasifikasi norma pernorma, misalnya norma yang mengatur tentang ruang lingkup hak cipta akan ditelusuri dalam pasal-pasal undang-undang hak cipta nasional, sebelum ditransplantasi norma semacam itu akan dilihat dalam Auteurswet 1912 Stb No.600 atau di berbagai Konvernsi Internasional yang mengatur tentang itu. Setelah dibandingkan dengan menempatkannya dalam satu matrik yang sederhana akan dilihat perbandingannya. Kesamaan pada bunyi norma, akan mengantarkan pada kesimpulan bahwa transplantasi dilakukan 100 %, begitu setrusnya. Kemudian tidak berhenti di situ saja, penarikan azas hukum yang tersembunyi dibalik norma hukum itu juga dilakukan sekaligus tentu saja ini dilakukukan melalui metode abstraksi. Untuk selanjutnya kedua asas hukum itu dibandingkan antara hukum nasional dengan hukum yang bersumber dari hukum asing. Keduanya kemudian dihadapkan untuk kemudian dipertemukan dengan metode ”Nuances” menurut kerangka pikir Mahadi. Misalnya ada norma hukum yang memiliki kecenderungan (ideologi ekonomi) kapitalis yang dicangkokkan ke dalam undang-undang hak cipta nasional, sedangkan di sisi lain Pancasila menganut (ideologi ekonomi) kerakyatan, keduanya dicarikan titik temu, dicarikan nuansa (nuances) norma- 119 norma itu tidak saling berbenturan. Norma-norma undang-undang hak cipta yang bertentangan nilai-nilai Pancasila itu disarankan untuk diubah dengan norma yang sesuai dengan kepribadian bangsa, akan tetapi dihindari kecenderungan konservatif, dengan merangkum pluralisme yang ada. Norma hukum konkrit yang direkomendasikan tidak boleh berujung pada penciptaan mitos pendewaan bangsa sematamata (commit nationally), akan tetapi menyahuti pula kepentingan global (think globally), dengan pengakuan pada pluralisme hukumhukum lokal (act locally). Formula seperti apa yang tepat untuk dapat menyahuti itu, hal itu akan menjadi rekomendasi penelitian ini setelah menemukan sesuatu yang baru (something new). Dalam kerangka yang lebih luas, analisis diarahkan juga untuk melihat proses legislasi yang dilakukan, dengan menguji data berupa memory van toelichting (asbabun nuzul) yang melatar belakangi kelahiran Undang-undang Hak Cipta dari waktu ke waktu. 2.1.Bahan Hukum Bahan hukum dalam studi penelitian doktrinal ini adalah sebagai berikut : a. Auteurswet Stb. No. 600 Tahun 1912 b.Undang-undang No. 6 Tahun 1982 c. Undang-undang No. 7 Tahun 1987 d.Undang-undang No. 12 Tahun 1997 e. Undang-undang No. 19 Tahun 2002 f. Bern Convention g.Rome Convention h.Universal Copy Rights Convention i. The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) Convention. 2.2. Teknik Analisis Langkah pertama yang dilakukan dalam analisis data adalah, menginventarisir seluruh norma-norma hukum yang termuat dalam Undang-undang Hak Cipta, meliputi Auteurswet Stb. No. 600, Undang-undang No. 6 Tahun 1982, Undang-undang No. 7 Tahun 1987, Undang-undang No. 12 Tahun 1997 dan Undangundang No. 19 Tahun 2002, The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) Agreement. Proses selanjutnya adalah mebandingkannya dengan menempatkan dalam matrik. Analisi dilakukan dengan menacri persamaan dan perbedaan dari kedua norma hukum yang 120 dibandingkan itu. Pada saat bersamaan dilakukan juga analisi dengan menggunakan metode abstraksi guna menarik asas-asas hukum yang “tersembunyi” dibalik atau di belakang norma hukum itu. Prosesnya bertolak dari premis-premis norma hukum positif yang termuat dalam undang-undang dan norma hukum asing tersebut, dengan teknik analisis interpretatif induktif. Interpretatif dilakukan dengan cara membuang hal-hal yang bersifat khusus untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat umum abstrak. Teknik ini juga dikenal sebagai teknik pengabstraksian dengan metode analisis induktif. Metode bernalar induktif akan selalu ditempatkan pada posisi mendahului melalui pengamatan terhadap pernyataan-pernyataan proposisional yang termuat dalam norma peraturan perundang-undangan hak cipta yang disusun sebagai premis-premis dan kemudian kesimpulannya ditarik melalui prosedur induktif. Dengan memanfaatkan proposisi-proposisi hasil pengamatan, maka akan diperoleh proposisi-proposisi baru sebagai kesimpulan induktif yang berdaya laku umum dalam bentuk asas hukum. Dalam dunia penalaran ilmu (hukum), asas hukum yang diperoleh secara induktif ini pada putaran berikutnya akan dijadikan sebagai proposisi pangkal (premis mayor) untuk mengembangkan pemikiran deduktif, spekulatif, guna membuktikan asumsiasumsi yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, yang pada gilirannya akan dipakai sebagai modal untuk memulai proses induksi berikutnya sebagai something new (norma hukum hak cipta yang sesuai dengan the original paradicmatic of Indonesian values cultural and society. Langkah selanjutnya adalah memperbandingkan (komparasi) asas-asas hukum yang ditemukan dalam berbagai-bagai peraturan perundang-undangan tersebut. Perbedaan pada tiap periodesasi undang-undang tersebut, akan menjadi kajian tersendiri pula dengan menggunakan pendekatan metode sejarah . Tentu saja teknik analisi yang dilakukan adalah teknik analisis yang mengacu pada perjalanan sejarah peraturan perundangundangan tersebut. Tiap suasana penggantian undang-undang itu, akan dianalisis situasi politik yang mewarnai dan melatar belakanginya. Informasi dan dokumen menjadi bahan rujukan utama seperti memory van toelichting, dan catatan-catatan yang mewarnai pembentukan undang-undang hak cipta nasional itu dari waktu ke waktu berdasarkan priodik dan itu akan menjadi dasar untuk pengujian hubungan antara variabel politik dan 121 variabel pilihan norma hukum yang tertuang dalam undangundang. Teknik ini lazim dikenal dengan “content analysis” (analisis isi). Teknik ini melulu menggunakan teknik analisis kualitatif, dengan kata lain menyampingkan teknik analisis kuantitatif, untuk sampai pada suatu kesimpulan sebagai temuan baru, sesuatu yang baru (something new). 3. Metode Penelitian Nondoktrinal Riset 92 Metode penelitian nondoktrinal riset dimaksudkan untuk mengetahui berbagai-bagai gejala empiris yang meliputi gejala sosiologis (struktur) dan gejala antropologis (budaya hukum) dan pilihan kebijakan politis yang berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut dari waktu ke waktu, mulai dari Auteurswet 1912 sampai dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2002. Hal ini untuk menjawab latar belakang politis yang mewarnai kebijakan hukum transplantasi dalam pembentukan Undang-undang Hak Cipta Nasional. Gejala-gejala empiris itu meliputi gejala kultural dan struktural dan politis serta ditarik juga dalam perjalanan sejarah yang panjang selama kurun waktu Auteurswet 1912 No. 600 sampai pada TRIPs Agreement 1994 yang akan mengungkapkan tentang pilihan politik hukum nasional dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan Hak Cipta Nasional. Selanjutnya dalam penelitian non doktrinal riset ini juga akan diuji tingkat daya laku (keberlakuan) Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta hasil transplantasi dalam perlindungan karya sinematografi yang dihubungkan dengan gejala sosiologis dan antropologis, meliputi budaya politik dalam kebijakan legislasi, budaya brirokrasi dalam arti penataan struktur pemerintahan yang menciptakan iklim birokrasi yang baik bagi upaya penegak hukum, budaya hukum para legal (dibatasi pada :polisi, jaksa, hakim dan kosultan hukum). Batasan tentang budaya di sini, lebih dari sekedar prilaku hukum, tapi juga menyangkut pandangan mereka terhadap polapola prilaku yang berkaitan dengan penegakan hukum karya cipta sinematografi 92 Lihat lebih lanjut, Soetandyo Wignjosoebroto, Penelitian Hukum dan Hakikatnya Sebagai Penelitian Ilmiah, Lihat juga Soetandyo Wignjosoebroto, Penelitian Hukum Normatif : Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal, Dalam Sulistyowati Irianto & Shidarta (ed), Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 83-141. 122 3.1.Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini ditetapkan di Kota Medan di geraigerai penjualan VCD dan DVD hasil karya sinematografi yang ditetapkan secara multi stage sampling (sampling bertahap) sehingga Kota Medan dibagi berdasarkan wilayah kecamatan dan tiap-tiap kecamatan ditetapkan 10 responden. Khusus untuk wawancara juga ditetapkan beberapa responden yang tinggal di Kota Medan. Geraigerai penjualan VCD dan DVD dipilih masing-masing 5 gerai tiap-tiap wilayah kecamatan untuk pedagang-pedagang kaki lima ditambah dengan masing-masing 3 gerai untuk pedagang kelas menengah yang tersebar di toko-toko dan masing-masing 2 gerai untuk pedagang kelas menengah atas yakni di plaza-plaza di pusat Kota Medan. Untuk pedagang kaki lima dan pedagang di rumah toko total responden ditetapkan sebanyak masing-masing 8 orang tiaptiap kecamatan meliputi : 1. Medan Amplas, 2. Medan Area, 3. Medan Barat, 4. Medan Baru, 5. Medan Belawan, 6. Medan Deli, 7. Medan Denai, 8. Medan Helvetia, 9. Medan Johor, 10. Medan Kota, 11. Medan Labuhan, 12. Medan Maimun, 13. Medan Marelan, 14. Medan Perjuangan, 15. Medan Petisah, 16. Medan Polonia, 17. Medan Selayang, 18. Medan Sunggal, 19. Medan Tembung, 20. Medan Timur, 21. Medan Tuntungan, Untuk gerai-gerai pedagang kelas atas, ditetapkan 4 plaza di Kota Medan yaitu : 1. Medan Plaza, 2. Medan Fair Plaza, 3. Sun Plaza, 4. Thamrin Plaza dan 5. Aksara Plaza. Selanjutnya untuk data yang akan diambil dari pihak aparat penegak hukum meliputi Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman. Kepolisian : Meliputi di wilayah 1. Medan area, 2. Medan Kota, 3. Medan Barat, 4. Medan Baru, 5. Medan Timur, 6. Medan Helvetia, 7. Percut Sei Tuan, 8. Patumbak, 9. Deli Tua, 10. P. Batu, 11. Kutalimbaru, 12. Polres Pelabuhan Belawan Kejaksaan : Ditetapkan di Kejaksaan Negeri Medan. Kehakiman : Ditetapkan di Pengadilan Negeri Kelas I Medan. 123 Penasehat Hukum : Khusus untuk kalangan penasehat hukum, ditetapkan di wilayah Kota Medan yang lokasi kantornya ditentukan secara acak. Konsumen : Khusus untuk kalangan konsumen, yakni masyarakat lokasi juga ditetapkan di seluruh wilayah Kecamatan Kota Medan dan dipilih 1 orang dari masing-masing konsumen yang berbelanja pada masing-masing gerai yang telah ditetapkan tersebut. 93 3.2. Sumber Data dan Informasi a. Data Sekunder yakni : - undang-undang - memory van toelichting penyusunan Undang-undang Hak Cipta Nasional. - jurisprudensi (putusan pengadilan) - buku-buku - karya ilmiah - majalah (jurnal) - artikel - data dari website internet b. Data primer yakni : - Kuesioner - Wawancara - Observasi 3.3. Penetapan Sampel Penelitian Sampel penelitian digunakan untuk pendekatan penelitian non doktrinal riset yakni dari kalangan penjual VCD dan DVD hasil karya sinematografi, ini dilakukan khusus untuk menjawab pertanyaan yang berkenaan dengan asal muasal barang yang dijual, status legalitas barang yang dijual, harga 93 Untuk observasi langsung lokasi penelitian ditetapkan di beberapa kota-kota di Eropa, Asia dan Asia Tenggara. Kota-kota di Eropa meliputi : Amsterdam, Den Haag, Brussel, Paris, Barcelona, Swiss, Venezia dan Frankfurt serta Istanbul, sedangkan untuk kota-kota di Asia observasi dilakukan di Jeddah selanjutnya di Asia Tenggara meliputi : Malaysia dan Singapura. Observasi ini hanya terbatas pada harga-harga jual masingmasing VCD dan DVD dan memastikan apakah di counter-counter luar negeri itu terdapat barang-barang illegal atau bajakan. 124 jual tiap-tiap keping VCD dan DVD, jenis-jenis karya sinematografi yang dijual (meliputi asal negara yang memproduksi cerita film tersebut dan jumlah konsumen yang membeli berdasarkan negara asal produksi film cerita tersebut), berapa pendapatan setiap harinya serta apakah pernah ada aparat penegak hukum yang melakukan penyidikan atau razia atas produk-produk yang mereka jual. Jumlah responden ditetapkan sebanyak 8 orang x 21 wilayah kecamatan yang ditetapkan secara acak dengan jumlah total 168 responden. Sedangkan untuk untuk responden kelas menengah atas ditetapkan masing-masing 4 orang x 5 geraigerai di plaza, dengan jumlah total 20 orang, sehingga total responden untuk penjual VCD dan DVD berjumlah 188 orang (untuk responden kuesioner). Dari 188 orang responden, 4 orang diantaranya dipilih sebagai responden untuk wawancara (namanya akan dirahasiakan). Untuk kalangan konsumen ditetapkan sebanyak 1 orang untuk konsumen yang berbelanja di tiap-tiap counter-counter atau gerai-gerai di wilayah kecamatan yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 168 responden ditambah 20 responden, jumlah total 188 responden. Selanjutnya untuk responden aparat penegak hukum ditetapkan : Kepolisian : Pihak Kepolisian yang meliputi di : 11 Kepolisian Sektor Wilayah Polresta Medan dan 1 Polres Pelabuhan Belawan masing-masing ditetapkan 2 orang. Jadi jumlah responden total 2 x 12 = 24 orang (responden untuk kuesioner). Dari jumlah 24 orang ini akan dipilih 4 orang sebagai responden wawancara. Kejaksaan, Kehakiman dan Penasehat Hukum Kejaksaan, Kehakiman dan Penasehat Hukum ditetapkan masing-masing 4 orang hanya untuk responden wawancara. Disamping itu ditetapkan juga 3 orang responden wawancara warga negara Eropa. 3.4. Penetapan Jumlah dan Penyebaran Responden Berdasarkan penetapan responden sebagaimana diuraikan di atas, dengan metode penetapan sampling bertahap (multistage sampling) maka karakteristik dan penyebaran responden dapat diuraikan sebagai berikut : 125 1. Pihak penjual VCD dan DVD a. Pedagang Kaki Lima Masing-masing 5 orang dari tiap kecamatan 1. Medan Amplas = 5 orang 2. Medan Area = 5 orang 3. Medan Barat = 5 orang 4. Medan Baru = 5 orang 5. Medan Belawan = 5 orang 6. Medan Deli = 5 orang 7. Medan Denai = 5 orang 8. Medan Helvetia = 5 orang 9. Medan Johor = 5 orang 10. Medan Kota = 5 orang 11. Medan Labuhan = 5 orang 12. Medan Maimun = 5 orang 13. Medan Marelan = 5 orang 14. Medan Perjuangan = 5 orang 15. Medan Petisah = 5 orang 16. Medan Polonia = 5 orang 17. Medan Selayang = 5 orang 18. Medan Sunggal = 5 orang 19. Medan Tembung = 5 orang 20. Medan Timur = 5 orang 21. Medan Tuntungan = 5 orang Total = 105 orang b. Gerai ruko Masing-masing 3 orang dari tiap kecamatan 1. Medan Amplas = 3 orang 2. Medan Area = 3 orang 3. Medan Barat = 3 orang 4. Medan Baru = 3 orang 5. Medan Belawan = 3 orang 6. Medan Deli = 3 orang 7. Medan Denai = 3 orang 8. Medan Helvetia = 3 orang 9. Medan Johor = 3 orang 10. Medan Kota = 3 orang 11. Medan Labuhan = 3 orang 12. Medan Maimun = 3 orang 13. Medan Marelan = 3 orang 14. Medan Perjuangan = 3 orang 15. Medan Petisah = 3 orang 126 2. 3. 4. 5. 6. 16. Medan Polonia = 3 orang 17. Medan Selayang = 3 orang 18. Medan Sunggal = 3 orang 19. Medan Tembung = 3 orang 20. Medan Timur = 3 orang 21. Medan Tuntungan = 3 orang Total = 63 orang c. Gerai plaza 4 x 5 = 20 orang Masing-masing 4 orang dari 5 Gerai Plaza 1. Medan Plaza = 4 orang 2. Medan Fair Plaza = 4 orang 3. Sun Plaza = 4 orang 4. Thamrin Plaza = 4 orang 5. Aksara Plaza = 4 orang Total = 20 orang Konsumen (warga masyarakat) Masing-masing 1 orang konsumen pada 1 gerai Kaki Lima Gerai Kaki Lima = 105 orang Gerai ruko = 63 orang Gerai Plaza = 5 orang 1 x 188 = 188 orang Kepolisian 1. Medan Area 2. Medan Kota 3. Medan Barat 4. Medan Baru 5. Medan Timu 6. Medan Helvetia 7. Percut Sei Tuan 8. Patumbak 9. Deli Tua 10. P. Batu 11. Kutalimbaru 12. Polres Pelabuhan Belawan = 2 orang = 2 orang = 2 orang = 2 orang = 2 orang, = 2 orang = 2 orang = 2 orang = 2 orang = 2 orang = 2 orang = 2 orang = 24 orang Kejaksaan 4 orang wawancara di Kejaksaan Negeri Medan. Kehakiman 4 orang wawancara di Pengadilan Negeri Kelas I Medan Penasehat Hukum 127 7. 3.5. 4 orang wawancara di wilayah Kota Medan yang lokasi kantornya ditentukan secara acak. Responden wawancara warga negara asing sebagai pembanding. 3 orang yakni : - Ibrahim Bashel - Pauline - Ali Cetin Langkah-langkah teknis pencarian atau pengumpulan bahan uji/data a. Data Sekunder, dikumpulkan melalui penelusuran kepustakaan dengan menggunakan buku-buku, hasil penelitian terdahulu, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, majalah ilmiah (jurnal) dan bahanbahan kepustakaan tertulis lainnya sebagai instrumen penelitiannya. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi-studi arsip dan studi-studi kepustakaan yang dilakukan sendiri atau dengan bantuan orang lain. b. Data primer, dikumpulkan melalui teknik wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai instrumen penelitiannya dan melalui kuesioner dengan mengggunakan angket/daftar pertanyaan yang bersifat kombinasi (tertutup dan terbuka) sebagai instrumen penelitiannya. Data primer juga diperoleh melalui hasil observasi langsung. Teknik pengumpulan data primer sebahagian dilakukan sendiri, sebahagian menggunakan orang lain atau informan. 3.6. Teknis Analisis Teknik analisis data yang bersumber dari wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut : a. Untuk data yang diperoleh dari hasil wawancara dilakukan penyederhanaan semua bahan yang terkumpul kemudian diklasifikasikan ke dalam kelompok-kelompok tertentu sesuai dengan variabel atau materi yang diteliti. b. Hasil wawancara yang telah diklasifikasikan dihubungkan dengan bahan yang diperoleh dari data 128 sekunder seperti memory van toelichting, hasil penelitian terdahulu, buku-buku ilmiah dan jurnal ilmiah c. Analisis selanjutnya tidak dilakukan berdiri sendiri tetapi dihubungkan dengan hasil penelitian doktrinal riset yang telah diperoleh sebelumnya (menghubungkan hasil wawancara dengan asas-asas hukum yang ditemukan). d. Kesimpulan akan diperoleh dari persemaian semua data yang ditemukan dalam butir a, b dan c di atas. Teknik analisis untuk penelitian non doktrinal riset untuk menguji penerapan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 hasil transplantasi dalam bidang perlindungan karya sinematografi, yang telah diwujudkan dalam bentuk Video Compact Disc (VCD) atau Digital Video Disc (DVD). Pengujian variabel-variabel penegakan hukum itu dibatasi pada 7 (tujuh) subyek hukum yaitu : 1. Pihak penjual VCD dan DVD 2. Konsumen (warga masyarakat) 3. Kepolisian 4. Kejaksaan 5. Kehakiman 6. Penasehat Hukum 7. Responden wawancara warga negara asing sebagai pembanding. Teknik analisis data dalam penelitian ini disesuaikan dengan kebutuhan dan pilihan (metode) untuk menjawab permasalahan. Rancangan analisis data dengan metode non doktrinal riset, dianalisis melalui tahapan sebagai berikut : a. Memberikan kode-kode tertentu (coding) pada lembaran kuesioner untuk kemudian data dikelompokkan/diklasifikasikan sesuai dengan variabelvariabel yang telah ditetapkan. b. Data yang bersifat kuantitatif (baik yang diperoleh dari wawancara, kuesioner yang merupakan data primer maupun data skunder) kemudian ditabulasi, dikelompokkan kemudian dimasukkan ke dalam tabel frekuensi selanjutnya diberi penafsiran secara kuantitatif dan kualitatif. c. Data yang bersifat kualitatif baik primer maupun skunder, dikelompokkan kemudian diberi penafsiran secara kualitatif. 129 d. Dalam memberi penafsiran dilakukan penyilangan antara data yang satu dengan data yang lain, untuk kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan akan ditarik dengan mempertemukan hasil-hasil yang dicapai dalam kedua pendekatan itu (doktrinal dan non doktrinal riset) dan dipadukan dengan data dan informasi yang bersumber dari dokumen-dokumen serta literatur-literatur yang memiliki keterkaitan dengan isu transplantasi hukum asing ke dalam undang-undang hak cipta nasional. Hasil dari keduanya ditarik menjadi suatu kesimpulan sebagai suatu penemuan baru (somethings new) yakni menemukan prinsip-prinsip hukum yang bersumber dari nilai-nilai paradigma sosial budaya Indonesia asli (ideologi Pancasila), untuk kemudian dijadikan sebagai landasan berpijak dalam setiap aktivitas legislasi nasional dan aktivitas penegakan hukum agar hukum tersebut dapat melindungi kepentingan nasional (commit nationally), berakar pada sosio-kultural masyarakat Indonesia dalam arti dapat mengakomodir hukum-hukum dan kebiasaan local (act locally) tanpa harus terkucil dari pergaulan internasional dalam arti mampu mengikuti arus perkembangan globalisasi (think globally). Dari hasil temuan baru itu akan melahirkan rekomendasi, langkah-langkah politik hukum seperti apa yang mestinya ditempuh oleh negeri ini ke depan. 130 CHAPTER II THE DYNAMICS OF THE HISTORY OF LEGAL POLICY IN THE TRANSPLANT OF COPYRIGHT LAW A. Introduction The existence of copyright law in Indonesia these days is inseparable from the history of the legal policy since the days of the Dutch East Indies (and even earlier) to post-independence. 94The effort to establish the order of Indonesian legal system was a political effort that was consciously done by implementing policies that were rooted in the transformation of the original Indonesian culture and combined with a foreign legal culture with all the successes and failures. This cultural transformation implies that the legal transplants were also part of the political system and culture which was derived from the history in Indonesian civilization. In essence, there is not a legal product that was born in Indonesia which was not derived from the process of cultural transformation that stem from diverse cultures and transplantation of foreign cultures in a process known as acculturation and enculturation. Since the beginning of the development of the Indonesian legal system, which was derived from colonial law, as Soetandyo Wignjosoebroto said95 it was strongly influenced by the development of liberalism policies which try to open the potential opportunities for private capital of Europe in order to be implanted into a large companies in the colony (on the other hand remained also to protect the indigenous people’s right or the rights of indigenous people’s traditional agriculture). The protection was given by effecting the enactment of law for them by enforcing the Adat law. The formula which was used by the Dutch government was to divide the three segments of the population in the area of Dutch East Indies, which was:96 1. European group that is equivalent to the European. 94 Before the entry of the Dutch colonialism government, the social order in Indonesia has a genuine legal form of customary norms, religious norms, and custom norms which was called as adat recht by Van Vollenhoven , see Ter Haar, Asas-asas dan Tatanan Hukum Adat, Mandar Maju, Bandung, 2011, 95 Soetandyo Wignjosoebroto, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 1994, p.3 96 Through Article 75 old RR and then converted to the new RR article 75, which had previously been written in Article 6-10 AB and finally with Article 131 and 163 IS 131 2. Foreign east group / vreemde oosterlingen (Foreign east such as Chinese, Arabic and Indian) 3. Bumi Putera / Inlander group (native Indonesian Population) Against these three segments of population, different kinds of law applied. For European group that is equivalent to the European, European law that was Dutch law which was rooted in the legal tradition of Indo-German and Roman-Christian which was updated through the various revolutions that later in the field of civil law loaded in Burgerlijk Wetboek and Wetboek van Koophandel or better known as the book of Commercial Law was applied. While for foreign east group, for majority, the Dutch Civil law was applied except for adoption and partnership. At last for Bumi Putera group, Adat law, their customary or their religion, was enforced, or known as Godien Stigwetten Volkinstelingen en Gukuedreken. There was an effort from Dutch East Indies government to align the rule of law in their country with the law in force in the colony. This policy later known as the principle of concordance, that was to equalize the law in force in the Netherlands with law in force in the Dutch East Indies colony. Although then the application of the principle is met with resistance from the Dutch’s own legal scholars such as Van Vollenhoven and Ter Haar. 97 In the field of intellectual property rights, the effort to codify and European law unification in the colony was run by enacting the law which was scattered sporadically (which was not codified in the book of Civil law and Commercial law) in their own country which were the laws about brand, patents, and copyrights. The copyrights law in Netherlands that time was the law which was derived from the copyrights law in France brought by Napoleon’s expedition. In the time of Dutch colonialism, this law was known as Auteurswet Stb. 97 See more, Soetandy Wignjosoebroto, Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, ELSAM, Jakarta, 2002, p.266. The story began from European officials who were recruited to fill positions in the colonial administration and for the necessary special education in various cities in Netherlands which was in Leiden, Delf, and Utrecht. They were taught mostly about the law, language, customs, and institutions of the society in the colony. In the three cities with well operated education, Leiden was recorded as the greatest and the most influential because Rijks Universiteit domiciled in Leiden was becoming a center of a liberal way of thinking that embraces ethical political line when dealing with the affairs in the colony. But Leiden surprisingly was not in line with the plans of the government official to run the Dutch Indies Government legal policies. And among the people who failed the attempt, were Van Vollenhoven and Ter Haar. And then through these two people, Indonesian Indigenous people finally had their own law known as Adat Rechts or Adat Law which was used for the first time by Snouck Hurgronje in his book, De Atjech hers and het Gajo Land. 132 1912 No. 600, was enacted in Indonesia with the concordance principle. The enactment of this law with the concordance principle created a legal pluralism even wider, for the cultural variety of that legal pluralism was existed earlier in Indonesian social order itself that time. The pluralism appeared because of the variety of tribes, religions, and territorial and the regulations were made based on this condition. It can be said that the impact of the dynamics of the Dutch East Indies government’s legal political choice, until today, has produced a product of legal pluralism that meets no ending. And also, after post-independence, the government of Indonesia made its own choice of legal policy in order to fulfill the demand of legal system in the time of post-independence in Indonesia. It seems like that the political factors, can never be completely detached from the activity in drafting the rule of law or legal system in Indonesia. The influences of foreign political pressure kept influencing the policy of legal development in Indonesia. Especially after the ratification of GATT/WTO 1994 as an instrument in economic globalization (or in the other field) which put Indonesia in a condition to adjust some regulations in the field of intellectual property right especially in the field of copyrights. The factors that influence the political choice are lack of control of the capital in Indonesia, lack of the ability to master the science and technology, human resource in Indonesia, and a poor management system in Indonesia. These are, which according to M.Solly Lubis, as a weakness which is possessed by Indonesia. It was put into words:98 They, (Industrial country), have and in charge of systematic advantages in three things: capital (funds and equipments), sophisticated technology and rapid and systematical management advantages. Our weakness and dependence in those three things, were also a prove of our weak autonomy, and this dependence was the cause of our inability to avoid open or covert interventions and dictations from another countries towards us. Economical exploitation, political domination, and cultural penetration can be seen everywhere. These three targets were thre main targets of imperialism colonialist and capitalist. 98 Look further M.Solly Lubis, Serba-Serbi Politik Hukum, PT.Sotmedia, Jakarta, 2011, p. 97. Look also Sritua Arief & Adi Sasono, Indonesia Ketergantungan dan Keterbelakangan, Mizan, Jakarta, 2013 133 The domination of foreign economic policy in Indonesia was actually not begun at the time of the ratification of conventions which are related with international trade such as GATT/WTO and the conventions under the GATT/WTO. The competition of the countries which today are the ruler of the world’s economic system which also incorporated in the industrialized countries like G-8 and G-20 was started with a long journey of history. The event that led to World War II can not be separated from the struggle of economic resources in the world. The expansion of European countries to Asia, such as United Kingdom to India, Burma, Hong Kong and Malaysia, France to IndoChina (Laos, Vietnam, Cambodia) Netherlands to Indonesia and even Unites States with its allies, UK, France, Netherlands, participated to control the activity in Pacific region. Those industrial countries, including Japan, although were at lost in East Asia War against the countries in allies (USA and Europe), their domination in economical politics is growing stronger each day until today. The record from Stephen E. Ambrose and Douglas G. Brinkey, 99 gave us an enlightenment that can be concluded that the power of economical politics in Asia will be still under the power of Western countries (USA and Europe). On the other side of the world the United States, in combination with the British, French and Dutch, still ruled the Pacific, American Control of Hawaii and the Philippines, Dutch control of the Netherlands East Indies (N.E.I., today’s Indonesia), French control of Indochina (today Laos, Cambodia (Democratic Kampuchea ), and Vietnam), and British control of India, Burma, Hong Kong and Malaya gave the Western powers a dominant position in Asia. Japan, ruled by her military, was aggressive, determined to end white man’s rule in Asia, and thus a threat to the status quo. But Japan locked crucial natural resourced, most notably oil, and w as tied down by her war in China. The introduction of copyright law in Indonesia is one of the examples of a conscious political choice which was made by the Dutch East Indies government until post-independence through political choice of law transplantation into the copyrights law which was 99 D Stephen E. Ambrose and Douglas G. Brinkey, Rise to Globalism, American Foreign Policy Since 1938, Penguin books, London, 2011, p. 1 134 enacted in Indonesia (In the time of Dutch East Indies) or in the Republic of Indonesia (post-independence). B. Auteurswet Period Stb No. 600 (1912 – 1982) Before the enforcement of Auteurswet 1912 Stb No. 600 in Indonesia, this country was not a country with a legal vacuum condition, especially in the field of copyrights. Measured by the normative standard from Meester in de rechten, (Law graduates from Netherland), we can see that Indonesia did not have any legal norms that time. If law was approved to be some sets of rules to regulate the behavior and actions of the society, then actually, Indonesian society that time, did have what is called as law. But if the point of view is that the legal sanction to the violation of norms was given by the ruler, or the norms must be made by a official ruler who was born from a legal formal norm based on modern democracy principle, and the application of the sanction was based on procedural law which subject to the regulations with the purpose of protecting human rights, then we can infer that Indonesia did not have law. The terminology about the existence of law was based on an existing terminology at a group of society who depended on the territory and the times where the values was located and enforced. The adage stated that “ubi societies ibi ius” is an indisputable axiom which means where society is, there is law. The society will be extinct automatically when there is no law in the life of the community, or according to the term stated by Djojodigoena, 100there is no ugeran that can be used to determine how to behave. The time of Dutch colonialism was lasted for three and a half centuries in Indonesia. The development of social dynamics and politics, including legal policy and economical politics and also cultural politics is somewhat being influenced by the colonial atmosphere. The Dutch legal policy to duplicate (with concordance principle) the legal norms, which was enforced in their country to the legal norms enforced in the colony, did not succeed. The enactment of Auteurswet 1912 Stb. No. 600 was one of the examples in duplicating the law from 100 Djojodigoena, Reiorientasi Hukum dan Hukum Adat, Gajah Mada, Yogyakarta, 1958, p.8-9. An ugeran is a law that charged an obligation and prohibition, while an anggaran is a law, that stated a condition. Both have a relation to a system or order. Anggaran is to determine, to record what is existed in the nature, so logically it is posterior to the system, and the ugeran is meant to limit the attitude, behavior, and human action in order to create a basic system in the society, so logically it is anterior to the system. 135 Netherland to the colony. Although the substance of legal norms in the Auturswet 1912 Stb.No 600 was enforced and had already fulfilled the criteria of the enactment (that was to place it in the Statute Book of Dutch East Indies (Wet van 23 September 1912, Staatblad 1912-600) effective since 23 September 1912) but the norms were failed to be applied. The failure was characterized by the fact that the arrangement and law enforcement had not actualized in line with expectations and its purpose ideologically, normatively, and sociologically. This could be seen in the books published by Balai Pustaka Publisher (In this era, Balai Pustaka publisher was a stated-own enterprises) which actually were books that translated from authors from Europe, but in the publishing process, the publisher from Balai Pustaka did not ask for approval to translate and to publish the books neither to the authors, nor to the original publishers as the copyrights holder. To mention, some of the translated books, are: L’avare, a French author, adapted by S. Iskandar entitled si Bakhil (1926) ; Le Medicin Lui, also by Moliere, adapted by Moh Ambri entitled Si Kabayan jadi Dukun (1932). Probably another hundreds of tittles were published without any approval from the copyrights holder.101 Although the translation by Balai Pustaka publisher was done with a good intention and with the purpose to enrich the treasure of literature for Indonesian society, but clearly according to Auturswet 1912, a non- permissible translation was a violation of law. Except, the translation was done from books which has already belonged to public (public domain), as long as the author’s name and the original title is mentioned, since the moral rights was still attached to the creations. In the time of Dutch colonialism, following the Netherlands, the Dutch East Indies was registered as a member of Bern Convention. It meant that Indonesia was subject to International Convention about 101 Sumardjo, Jakob, Dari Kasanah Sastra Dunia, Penerbit Alumni, Bandung, 1985, p.133, which written the list of translated novel from Balai Pustaka “before the war” and “after the war” in number of 174 tittles ; Bdg also Wink, TH, Undang-Undang Hak Pengarang, G. Kolf & Co, Bandung, 1952 p. 23 and Ajip Rosidi, Undang-undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam, Penerbit Djambatan, Djambatan, Jakarta, 1984, p. 4 Bdg also J.P. Errico stated that the arrangements of law and copyrights of countries likes Singapore, Malaysia and Indonesia is strongly influenced by the concept of intellectual property rights derived from western countries. And then these three countries and the neighboring country, were stated in a very interesting explanation: These nations were colonies of the West (notably the United Kingdom and the Netherlands) much longer than the neighbors, and therefore have had their development o intellectual property protection, industrial policy and technological expansion, controlled by the West. In fact some countries, like Singapore, have no independent systems of intellectual property protection to this day. 136 the protection of copyrights. There are not many records that reveal events about copyrights infringement in the time of Dutch colonialism. But the records about how Auteurswet 1912 Stb. No. 600 finally had to be replaced, in many explanations can be said that at that time, many violations towards copyrights had happened. Those violations were not merely happened because the ineffectiveness of the law enforcement in the field of copyrights, but they were because of cultural affairs, politics affairs, and the economical condition of the society in Dutch East Indies that time. 102 A relative copyright protects the interests of the creators in the field of book publishing and cinematography at the beginning of Auteurswet 1912 Stb. No. 600 enactment in the colony by the Dutch East Indies government, was not an urgent matter to be protected. This was marked with not much of publishing and production effort in the field of cinema which operated in The Dutch colonial territory that time. 103 In the time of Japanese occupation, the situation of law enforcement was tinged with the political situation and the turbulent 102 Let us just consider that the colonialism had caused a lot of wars with local scale that happened in every territorial in Republic of Indonesia. The priority to focus on the aspects of law enforcement by the Dutch colonial government in the field of civil law and also in the field of business , where Indonesian society that time, subjected to Adat law, unless those who were willing to subject themselves is voluntary, made the choice of law enforcement in the field of copyright by the apparatus of law enforcement in the time of Dutch East Indies was not as the highest priority. The fields of copyrights which were protected that time were mostly unknown in Indonesian civilization. Such as copyrighted works of photography, books, cinematography, paints, were known to a very few of people. Whereas copyrighted works such as dance, batik, which were the original copyrighted works of Indonesian people, were not a big problem, or considered as a violation of copyright law if the work was used by the other Bumi Putera without the approval from the creator. It happened in the time of Dutch colonialism, and it was being continued until the beginning of post-independence. The violation of copyright law was not considered as a felony that preoccupied the jurist. 103 Activity in the field of cinema for instance just began in 1926, that was with the production of a movie entitled Loetong Kasaroeng then Eulis Atjih in 1927, and consecutively in 1928 Lily van Java, Nyai Dasima in 1929. Until in 1942 that was the beginning of the Japanese occupation, The Dutch East Indies film industry did not much involve Bumi Putera population, especially among the directors . After the Japanese occupation, directors from Indonesia began to emerge, such as Raden Arifin, Rustam Sutan Panidih, B. Koesoma and Inoe Perbatasari. Because of that in the field of copyrighted works of cinematography , an original Indonesian population was not considered as an important matter to be subjected to Auteurswet 1912 Stb. No 600. Beside that, the technology to reproduce the copyrighted works of cinematography unlawfully, is not as advanced as at the time of the discovery of optical disc technology. See more Taufik Abdullah, Misbah Y. Biran and S.M. Ardan, Film Indonesia, (19001950), Jakarta, Dewan Film Nasional, 1993, p. 87. 137 war, so that the law enforcement (not only in the field of copyright but also in another fields did not become priorities that time. The supreme leader of Gunseikhanbu, (military government of Japan) on the former Dutch colony land, focused more on military efforts to win the East Asia War, so that the occupation for three and a half years did not produce any legal protection in copyright aspect. In that era, there was a cultural center established (Keimin Bunka Shidosho) which dealt with the aspects of Indonesian culture, but more geared to the interest of Japan and the library that was developed in the cultural center dealt more with archival records and books seized from the Dutch Indies government. It can be ascertained that the legal protection of copyright works of the period was not completely focused on the provision of law which still has a valid power, the Auteurswet 1912 Stb. No. 600. In the year of 1944, the Japanese occupation ended, coincided with the end of the East Asia War. The 17th August 1945 proclamation of the Indonesian Independence day, echoed formally throughout the nation, was the ending of colonialism regime in Indonesia. Indonesia immediately constructed its own legal order. In the process of the legal order construction, for the first time on the 18th August 1945, Indonesia could apply the basic law of its country, the Constitution of Republic Indonesia. While the other legislations or laws, were still in preparation. But in an independent country, a legal vacuum must not be happened. Considering this situation, Indonesian Independence preparatory committee, or known in Indonesia as PPKI, arranged the Constitution of Republic Indonesia, and established in the transition law to continue using the laws from the colonial legacy. This transition provision is written in Article II Transition Law in Constitution of Republic Indonesia 1945:104 All state agencies and regulations existed still apply as long as the new one is not yet to be applied according to this Constitution. 104 The same transition law is also written in the constitution of Indonesian Republic Union, the interim of Constitution of Republic of Indonesia. Basically it has the same meaning with the transition provision in the constitution of Republic Indonesia which s written in Article 192 in constitution of Indonesian Republic Union and Article 142 in interim of Constitution of Republic of Indonesia. Because of that, Auteurswet through these transition laws which were written in three different constitutions which ever enforced in Indonesia is still applied although it is a legacy from the Dutch government. Auteurswet, legally, is still a Positive Law for copyright arrangement in Indonesia. After approximately 70 years of the enactment of Auteurswet 1912, by Indonesia as a independent country, national legislation of copyright, Act Number 6 of 1982 was put in place. 138 To strengthen and explain the realization of the Transition Law by the President at that time, it was crucial to establish Presidential Regulation No.2 10 October 1945 which the first provision citation is: Every state agencies and regulations existed until the establishment of Republic of Indonesia on 17 August 1945, according to the Constitution of the Republic, as long as the new one is not yet to be applied, is still valid providing that it does not contradict to the mentioned Constitution of the Republic. Referring to the above regulation, Auteurswet 1912 Stb. No. 600 is one of the remaining law of Dutch colonialism legacy which the validity still continued until 1982. Since Indonesia gained Independence on 17 August 1945, there were 37 years of interval until the remaining Wet of Dutch colonialism legacy was changed. During the interval, the law enforcement in the field of copyright did not show any good news. Copyright infringement specifically in the field of book publication continued during that period. Even so, during the 70 years of the enactment of Auterswet 1912 Stb. No. 600 at least in the history record, this wet became the basis of the establishment of national copyright law. In International dimension, Indonesia as the region of Dutch East Indies during the enactment of Auterswet 1912 Stb. No. 600 legally subject to Bern Convention. After 1 August 1931, the convention was declared to be valid in the Dutch East Indies territory which is written in Staatsblad 1931 No.325. The Bern Convention which was declared as valid was the Bern Convention 1886 that had been revised in Rome on 2 June 1928. This text was declared binding the colonies of Dutch East Indies. Therefore during the reign of Dutch East Indies, there were 2 staatsblad that apply concerning copyright protection. The first staatsblad is Staatsblaad 1912 No. 600 concerning Auteurswet that was about protection of copyright in colonial territory and the second was Staatsblad 1931 No. 325 that was internationally Copyright protection that subjected to Bern Convention. During the Dutch colonial period, it was almost certain that the rules about copyright were more than creating the status quo as depicted by Hendra Tanu. 105 The status quo, or the situation which led to ineffectiveness of 105 Hendra Tanu Atmadja, Hak Cipta Musik atau Lagu, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2003, p. 41. Hendra Tanu mentioned that Copyright Law in the Dutch Colonialism, Japanese occupation, even until proclamation of Indonesia Independence did not take place in law enforcement. He said that that law was dead or not applicable. 139 Copyright laws made by the government of Dutch East Indies, according to Otto Hasibuan caused by two factors. The first is because the law itself contains many flaws in substance which includes the regulation and the sanctions. Second, after the proclamation, Indonesian government had a desire not to protect copyright as it should be. The Signs of Indonesian government was not willing to protect copyrights can be seen, which is according to Otto Hasibuan: 106 1. On 1958, during the reign of Djuanda Cabinet, Indonesia declared to sign out of Bern Convention (With the intention that Indonesia can freely perform various knowledge transfer activities from abroad to domestic by translating, imitating, or copying foreign creation). 2. The government let Balai Pustaka publisher violated the existing copyright laws. 3. Government, particularly law enforcer let Indonesian authors retell foreign works without any approval. 4. Although aware that the Auteurswet 1912 is inappropriate and contains many flaws, government and the House of Representatives were not serious in creating the new Copyright Laws. The reason for Indonesian discharge from being a member of Bern Convention is more than what Otto Hasibuan expressed. Indonesian political situations at the time were attempting to reclaim West Irian. If the membership of Indonesia in Bern Convention based on the attachment to the registration conducted by the Dutch government, then it means that Indonesia recognize Dutch sovereignty. Because of that, Juanda as the leader of the cabinet (that time Indonesia adhered the cabinet of ministry) took political steps to sign out from Bern Convention. Moreover, the cultural factors (legal culture) and sociological factor, also influenced legal behavior of Indonesian people. Legal aspects which were not rooted culturally and structurally in Indonesian society would be hard to be enforced. That was the consequence of legal transplant. Experience in western law transplantation in history of legal establishment in Indonesia (not only in the field of copyright) in a lot of cases, was having failures because of the principles which were the background of western law, did not similar with the principles which were firmly rooted in the legal norms of Indonesian people. Although in a long term of period, efforts to 106 Otto Hasibuan, Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighboring Rights and Collecting Society, Alumni, Bandung, 2008. 140 accelerate the European law transplantation process to the colony, said Soetandyo Wignjosoebroto,107 as an Europeanization of the colonial legal system that finally happened although it took a pretty long time. Such as the enactment of book of civil law (BW), book of commercial law (WvK), book of criminal law (WvS), criminal procedural law (HIR) and civil procedural law (RbG), all was done with the choice of legal transplants gradually and took time with three legal policies, that were: statement of application (topasslijk verklaring), equality of right (gelijk steling) and subject to voluntary (vrijwillige onderwerping). These policies were based on realistic consideration with various compromises between Dutch colonialism government with Indonesian people and the leaders. Although in the beginning it had been mentioned that an Europeanization to the colonial legal system met a lot of resistance including from their scholars.108 Another main reasons to the difficulty of Auteurswet Stb. No. 600 to be applied or enforced, was that the condition of original local culture that caused the difficulty for a foreign transplant law to develop. As a record Auteurswet 1912 Stb No. 600 was an enforced law for European group (vide Article 162 and 131 IS), Bumi Putera group might use the law based on 1854 regeringreglement 1854 with the institution vrijwillige onderwerping. Decades after the enactment of regeringreglement 1854 as written by Soetandyo proved that the institution vrijwillige onderwerping rarely used by Indonesian people which indicated that very few of people who were willing to expand the jurisdiction of European law. This fact showed us the difficulty of Indonesian people to let their own custom or culture go. They would rather to walk on what they believe as laws which were based on the original paradigmatic value of Indonesia culture and society. Those who were brave enough to leave the Adat law or their customary law, are those who came from local societies who were segmented by the divide and rule legal policy which was launched by Dutch colonialism government. A lot of records mentioned that the legal policies of European law legal transplant to Indonesian law which existed earlier 107 Soetandyo Wignjosoebroto, Op.Cit, 2002, p.259. The failure of Dutch colonialism government in running the Europeanization process from colonial law to the colony did not only because of the cultural barriers, but because of financial problem in the Dutch government especially after the enactment of Compatabileitswett in 1864 (Ind. Stb. No. 104) which stated that the finance for Dutch East Indies administration must be borne by the income of Dutch East Indies itself. But this finally compounded the development and institution of European law in the colony 108 141 would not always work well as expected. The policies to enforce the transplant law in Dutch colonialism can be seen not to be able to alter completely the legal perception of Indonesian people. Even in the court, a varied in concreto verdict which is often to be found indicates that there were variables of culture which were adhered by the offenders which cause discrepancy between the judges’ perceptions in making verdict.109 Auteurswet 1912 Stb. No. 600 was actually not enough just being supported by legal awareness of Indonesian people which was derived from the original paradigmatic value of Indonesian culture and society, because of that, in the enforcement of Auteurswet 1912 Stb. 1912. No. 600 must have a resonant with Indonesian people. So it could be understood why the European law had to be enforced with a firm external force. So it was not about severe or mild legal sanction. It can be proved here the truth about the effectiveness in control theory to control organizational life which was at a sustainable level would not work if the development of social structure, (the government organization in the time of Auterurswet 1912 Stb. No. 600 enactment) was not in line with the development of normative structure (the moral and legal awareness of Indonesian people). In this matter, it is interesting to see Seidman’s conclusion, which was achieved from his studies about British legal transplant into the colonies in Africa, which succinctly mentioned in the law of non transferability of law, Seidman mentioned:110 1. Laws are addressed to addresses (here called “role-occupants), proscribing their behavior. 2. How a role-occupant acts in response to rules of law is a function not only of their prescriptions but also of his physical environment 109 The enactment of the book criminal law which was designed by the Dutch for Indonesian people, during the post of the colonist minister Fransen van de Putte (1872-1874) was not also altered the whole native concept regarding what is bad and what needs to be punished. In court, what was meant by wederrechtelijk or unsure in criminal, always caused a variety in concreto verdict, in line with variety culture in society. It also happened in the enactment of Staatsblad 1862 No. 52 which required individuele contractsluiting based on the principle of freedom of contract, was not also altered the customary pattern of Indonesia society to not bind by ending the contract by trusting the contract completely to their leaders. This provision contained in the Staatsblad did not make Indonesian people understand about moral principles which was contained in pacta sunt servanda adage, see more Ibid, p. 260. 110 Robert B. Seidman, The state Law & Development, St. Maartin’s Press, New York, 1978, p. 36 142 and of the complex of social, political, economic and other institution within which he makes his choices about how to behave. 3. The physical and institutional environments of different sets of roleoccupants differ from time to time and place to place. 4. Therefore, the activity induced by the rules of law is usually specific to tie and place. 5. Therefore, the same rules of law and their sanctions in different times and places, with different physical and institutional environments will not induce the same behavior in role-occupants in different times and places. Although Seidman did not mention cultures and normative structures as one determined variable in the matter of the effectiveness of transplanted foreign law, but he was departing from a basic assumption about behavior of society by saying that someone’s legal behavior, will be determined more by his decisions and choices by considering the most favorable alternative. Then, it can be concluded that legal norm is just one of many institutional determinant which will influence the choice or decision of the society. Also, because of that, law which was derived from the transplant policy from foreign law, when it had to be run in a territory, it should be suspected that there would be variety in the acceptance of the law. Here, people would arrive at one conclusion that the transplanted law would not create the same effect as it had created in the origin place of the law. That is why Seidman mentioned that law can not be transferred from foreign place without “ripping apart” the whole institutional system which has become the context. Based on the explanation, it can be concluded that Auteurswet 1912 Stb. No. 600 which was rooted on European legal culture, derived from the Netherland which was brought by France expedition with a firm rule of law tradition, could develop in Indonesia through legal transplant policy which country was accustomed to the traditions of unpretentious law enforcement and subjected to the local discretion or wisdom. It is not lawlessness when artisan of batik imitated the pattern of batik which was made by his colleague in a society that has lived with family atmosphere. A dancer copies a movement from martial arts which is taught by his master in dancing or the martial arts is also not unlawful. Borrowing the theoretical framework stated by Seidman, the law of non transferability of law, then we can conclude that the concordance policy by the Dutch colonialism who enforced the Auteurswet 1912 Stb. No. 600 in the colony was a policy that contradicted with the basis of cultural values. In this matter, Indonesia 143 has to observe the truth that the rule of law concept is not always if only understood from law aspects, but the human aspects with every circle of law around, must also be understood. For this country was not established only to enforce “the rule of law”, but also the “rule of man”. Referring to this concept, it is not excessive if advised that the copyright law which is enforced today, derived from foreign law, with the choice of legal transplant policy, must be returned to the noble values which were implied in Pancasila ideology which is the original paradigmatic value of Indonesian culture and society. C. Period of Copyright Law number 6 of 1982 (1982 – 1987) Twelve days on April 1982 were such important days in the history of protection of copyright law in Indonesia. On that day, the copyright law which was from the Dutch Colonialism in period of 70 years which has become reference for the jurists in Indonesia, was ended in its domination. The wet which was recognized as Auteurswet 1912 Stb No. 600 was revoked and stated not applicable and as its substitution would be the Act number 6 of 1982. As an independent country with its sovereignty, it is not wise if the law enforced was flatly from the product of the colonial which for 350 years positioned themselves as imperialist country. Even though on 17 August 1945, Indonesia was managed to drive away the colonialist to leave Indonesia, but on the other side the law domination was not also ended at the same time the colonialism in Indonesia ended. That means that the atmosphere post independence was not an independent atmosphere in a whole meaning. The remains of colonial domination in the field of law was still being enforced. Even in the field of Copyright, the independence was actually meant independence on the next 37 years after Indonesia was managed to replace the position of the colonial product. The word “was managed to” was put in quotation mark because not all the legal norms originated by the Dutch colonial was really replaced. Beside the norms were still dominated the new Indonesian Copyright law, the weltanschung was still stained the spirit of the new Indonesian Copyright law. It cannot be denied that the Articles in Auteurswet 1912 Stb number 600 haunted the legal norms contained in the Act number 6 of 1982. This following matrix would show that the majority of norms contained in the Articles in the Act number 6 of 1982 were from Auteurswet 1912 Stb. No. 600. Matrix 1 144 Auteurswet 1912 Stb. No. 600 norms transplant into Act No. 6 of 1982 (Norms regarding Copyright Terminology) Regulated material Copyright Terminology Source : Auteurswet 1912 Act 6/1982 Copyright shall be a sole right of the Author or the right of those who are entitled to the right, on his creation, in the field of literary, science, or art to publish and duplicate, with remembering the limitation provisioned in the law (Article 1) Copyright shall be a privileged right for the Author or those who are entitled to the right to publish or duplicate or provide permission for that without abandoning the limitations referred to the enforced regulation (Article 2) Data Processed from Articles of Auteurswet 1912 Stb. No. 600 and Act No. 6 of 1982. Regarding the copyright terminology used in the Act number 6 of 1982 contained in Article 2 was similar with the copyright terminology contained in Auteurswet 1912 Stb No. 600. The difference was on the word “sole right” replaced with “privileged right”. Beside that the substance didn’t show any more difference. The legislator had no courage to put in philosophical value of Pancasila, such as the value the belief in the one and only God (Ketuhanan yang Maha Esa). The legislator had no courage to make a redaction that the copyright was a right born by the talent given by the God Almighty or born by the blessing from the God to the human. At a glance, the difference if the believe in one and only God value was put in and not, was not really obvious in normative juridical way. But by not applying those kind of values, it can be seen that the legislator just accepted the concept of Copyright contained in Auteurswet 1912 Stb No. 600 which was affected by the capitalism ideology which based on the Western values. It would bring consequences philosophically in searching hidden principle behind the legal norm Article 2 Act number 6 of 1982. If there would be a question regarding what legal principle was hidden behind the legal norm Article 2 Act number 6 of 1982, then the legislator could not provide answer except saying that the hidden principle behind the legal norm was the principle hidden behind legal norm Article 1 Auteurswet 1912 Stn Nom. 600 that was legal norms 145 based on capitalist ideology and Western law civilization. That is why this Article 2 in Act number 6 of 1982 was the result of a total transplantation from Auteurswet 1912 Stb no. 600. Matrix 2 Auteurswet 1912 Stb. No. 600 norms transplant into Act No. 6 of 1982 (Norms regarding Author Terminology) Regulated Material Author Terminology Auteurswet 1912 Act 6/1982 Unless proven otherwise, then what is considered as the author shall be the person who stated as it is or in that creation, or if the statement is not exist, person whom when the creation announced, stated as the author by the person who announced it. When there is no announcement regarding the author, when an unpublished verbal speech is being held, or when an unpublished music creation is being heard, then, unless proved otherwise, the person who is considered as an Author shall be the person who did the speech or the person who let hear of the music creation. (Article 3) A person or some people who in their togetherness by their inspiration gave birth a Creation based on intelligence, imagination, dexterity, skill, craftsmanship, poured in a typical and personal shape. (Article 1) Source : Data Processed from Articles of Auteurswet 1912 Stb. No. 600 and Act No. 6 of 1982. From the matrix above, it can be concluded that human have such high dignity in the process of confining a copyrighted work. The legislator had no courage to put in some redaction that in a process of creation “intervention from God” inspire every mind, imagination, dexterity, skill, and craftsmanship possessed by human. Why does the redaction of Article 1 regarding the Author terminology sound that way? This is because the legislator believed that the copyrighted work was born because of the “single, personal, typical skill” of the Author. The definition in Auteurswet 1912 Stb. No. 600 that only mentioned 146 the Author as the copyright subject without the words “based on his own intelligence, imagination, dexterity, ability and skill poured in a typical and personal shape” is much better. The divinity values are not also reflected in the provision in Article 1 the Act number 6 of 1982, and that means by not mentioning the divinity values at all as stated in Auteurswet 1912 Stb Number 600. Matrix 3 Auteurswet 1912 Stb. No. 600 norms transplant into Act No. 6 of 1982 (Norms regarding protected Creation) Regulated Material Protected Creation Auteurswet 1912 Act 6/1982 Protected Creation in literary, science or art by this Act shall be: 1. Book, brochure, newspaper, magazine, or all kinds of written works. 2. Creation of performance and dramatic music. 3. Verbal speech. 4. Choreography and pantomime Creations. Which the way of playing it regulated by a writing or such as it. 5. Music creation with or without any verbal. 6. Portrait, painting, building, statue, lithography, carving, and all kinds of picture of works. 7. Geographical maps. 8. Designs, sketches, plastically creatios, which connected with architecture, geography, or a picture of one place or other knowledge. Protected Creation in science, literary and arts, include: 1. Book, pamphlet, and all kinds of written Creation. 2. Seminar, lectures, speeches, and the similar creations. 3. Performance works such as music, karawitan musical, dance musical, wayang, pantomine, and another broadcast creation for radio media, television, movies and recording. 4. Music and choreography creation with or without text. 5. All kind of fine arts such as paintings and 147 9. Creations of photography and cinematography and creations done in that kind of way. 10. Artificial creations used in any handicraft and commonly all kind of works in the field of literary, science and art, with way or any shape (Article 10) statues. Architecture works. 7. Map 8. Cinematography works 9. Photography works 10. Translation, commentary, adaptation and the preparation of potpourri. (Article 11 paragraph 1) 6. Source : Data Processed from Articles of Auteurswet 1912 Stb. No. 600 and Act No. 6 of 1982. The kind of protected Creation in Act number 6 of 1982 also referred to the format and substance contained in Auteurswet 1912 Stb Number 600, even though there was some increase of the copyrighted works of native Indonesian society such as karawitan, pewayangan, even though the art of batik has not been attached in the protected creation as copyright. But by looking at the aspect of culture of Indonesia which confine a typical copyrighted creation has been put in the copyright protected object, it has already been the form of the original paradigmatic value of Indonesian culture and society. Does the entry of these two objects of copyright protection which are based on Indonesian culture was based on one deep study, or it was just a coincidence, has been a serious question. Because it turns out that Indonesian real creation such as batik art and martial art such as pencak silat, were missed from the attention of the legislator that time. Matrix 4 Auteurswet 1912 Stb. No. 600 norms transplant into Act No. 6 of 1982 (Norms regarding the time period of copyright) 148 Regulated Material Regarding time period of copyright Auteurswet 1912 Act 6/1982 As long as the Author live plus 50 years after his death (Article 37) As long as the Author live plus 25 years after his death (Article 26) Source : Data Processed from Articles of Auteurswet 1912 Stb. No. 600 and Act No. 6 of 1982. The time period of Copyright ownership was different in Auteurswet 1912 Stb No 600 and in Act number 6 of 1982, but the limitation still referred to capitalist concept. It was proven with the provision in Article 26 Act number 6 of 1982 which only lasted for 5 years, after that all Copyright laws born after the Act number 6 of 1982 referred back to Article 37 Auteurswet 1912 Number 600. That means, the time period of Copyright ownership still given to the Author as long the Author live, plus 50 years after his death. There was no courage of the legislator to put in redaction in the Article regarding this time period of copyright to be referred to Pancasila philosophical value that is the Humanity value and Social Justice value. The legislator had no courage to attach the social function of copyright as attached in Article 6 of Agrarian Principal Law of 1960 which stated that every right on land has social function. The Agrarian Principal Law of 1960 has arranged well the philosophical values contained in Pancasila. What can we concluded from the provision in Article 26 of Act number 6 of 1982 is that behind the norm of Article 26 still hidden the legal principles that based on capitalist ideology. Matrik 5 Auteurswet 1912 Stb. No. 600 norms transplant into Act No. 6 of 1982 (Norms regarding Copyright limitation) 149 Regulated Material Copyright Limitation Auteurswet 1912 Act 6/1982 By the name of the law the decisions or the laws released by the general authority, also by verdicts and administrational decision , shall not be considered as copyright. Also, there shall be not copyright on everything that is announced by or in the name of general authority, unless the right is stated protected both in in its general by the law, verdicts, or regulation, or in one specific condition with the announcement on the creation itself when the creation is being published. (Article 11). It shall not be considered as Copyright infringement a summary or an adaptation from newspaper or magazine on article, news, except in novels or romance without the consent from the Author or who entitled to the right, by the daily newspaper or other magazines, as long it is mentioned the newspaper or magazine source and there is no announcement that it’s a copyrighted work. Also regarding the writings regarding political concept. News and any color, shall not be copyrighted. (Article 15) Speech that spoken in It shall not be considered as copyright infringement : a. The Announcement and Duplication of the symbol of the nation or the song of the nation in general character. b. Announcement and Duplication of everything announced by or in the name of the Government, except when the copyright stated as protected both by the legislation or with a statement on the creation itself or when the creation announced. c. A taken over, both in a whole or in partial, news from the news office radio announcer agency or television and newspaper after 2 x 24 hours calculated since the first announcement of the news and its source must be completely mentioned. (Article 13) With requirement that the source must be completely mentioned, then it shall not be considered as Copyright infringement.: a. Any adaptation of another party as much as 10% of one unity from every adapted creation as a source to elaborate the proposed issues.. b. A taken over of a creation both in whole part or in partial in order to defend in or outside court. c. A taken over of creation by other party both in whole part 150 public and has not been printed and published mentioned by the person who did the speech. (Article 16) Limited duplicated creations in a few exemplars used for personal use for rehearsal and study. (Article 17) Creation of picture, paintings, buildings, lithography, carving and all kinds of pictures seen publicly if the creation is being duplicated if the process of the making showed a clear difference more than the real process of making. (Article 18) Pictures in any shape duplicated, announced, and published if the things relate to the jurist purpose to reveal any criminal act in order to establish public order. (Article 22) Source : or in partia; for the use of: 1. Seminars which only for the purpose of education and science. 2. Performance or staging without any fees. d. Duplication on creation in the field of science, art, and literary in braile for the use of blind except if the duplication was commercial. e. A limited duplication with a copy or similar process by a common library, science or education institution or a non commercial documentation center only for the use of its activity. f. Alteration done on architecture work such as building based on technical consideration (Article 14). For the purpose of public security and or for the faith the criminal proceeding, any portrait of anybody in any condition can be duplicated in any ways can also be duplicated and announced by authorized institution. (Article 21) Data Processed from Articles of Auteurswet 1912 Stb. No. 600 and Act No. 6 of 1982. The redaction of the Article regarding the limitation of Copyright as referred to Article 13, Article 14 and Article 21 Act number 6 of 1982 is a total transplantation of the provision in Article 11, Article 15, Article 16, Article 17, Article 18 and Article 22 of Auteurswet 1912 Stb No. 600. The legislator also has no courage to limit the Copyright in the Divinity values, Humanity values and Justice values or for example on the copyright which has not been regulated in this Act shall be subjected to Adat law. For example for the duplication and translation of scripture from any religion in Indonesia if done without consent from the translator or the publisher shall be considered as copyright infringement. 151 Matrix 6 Auteurswet 1912 Stb. No. 600 norms transplant into Act No. 6 of 1982 (Norms regarding non-Copyrighted Creation) Regulated Material Non Copyrighted Works Auteurswet 1912 Act 6/1982 By the name of the law, decisions and regulations released by the general authority also the verdicts and administrational decision shall not be considered as copyrighted works. Also, there shall be no copyright on anything announced by or in the name of general authorization, except when the right stated as protected both in general with laws, decision or regulation or in one specific condition with the announcement on that creation itself or when the creation published. (Article 11) There shall be no Copyright on: a. The result of open meeting of highest institution of nation or highest institution. b. Legislation c. Verdict or determination of the judge. d. The state speeches or government official speeches. P e. Arbitration (Article 12) Source : Data Processed from Articles of Auteurswet 1912 Stb. No. 600 and Act No. 6 of 1982. The provisions regarding non copyrighted works are the provision which adopted “flatly”. The legislators of Act number 6 of 1982 did not have to express their attention to formulate this article except enough by translating the provision of Auteurswet 1912 Stb number 600 to be made as redaction of Article in Bahasa Indonesia which will be poured in Indonesia Copyright law. These kind of Articles are still found in the Act number 6 of 1982. Matrix 7 Auteurswet 1912 Stb. No. 600 norms transplant into Act No. 6 of 1982 152 (Norms regarding the Prohibition of Copyright Use) Regulated Material Prohibition of the use of Copyright Auteurswet 1912 Act 6/1982 The prohibition to The Copyright Holder on publish any portrait someone’s portrait, to duplicate without the consent or announce his work, has to of the portrayed have a consent from the person (Article 20) portrayed person, or in 10 years The prohibition to after the portrayed person’s publish any portrait death, with the consent of his which is contradict heir (Article 18 Paragraph 1) with appropriate purpose (Article 21) Source : Data Processed from Articles of Auteurswet 1912 Stb. No. 600 and Act No. 6 of 1982. Regarding the prohibition of the use of the Copyright regulated in Article 18 Paragraph 1 the Act number 6 of 1982, was also adopted 100% from the provision in Article 20 and Article 21 Auteurswet 1912 Stb. 600. Also the regulation of moral right as regulated in Article 19 and Article 24 the Act number 6 of 1982 as provided in the matrix below, also based on the provision of Article 25 Aureurswet 1912 Stb No. 600. Matrix 8 Auteurswet 1912 Stb. No. 600 norms transplant into Act No. 6 of 1982 (Norms regarding Moral Right) 153 Regulated Material Hak Moral Auteurswet 1912 Act 6/1982 The prohibition to change the name of the Author, the name of the object of the creation and the object (Article 25) Copyright holder shall not be able to announce the Copyright on a portrait if the announcement contradicts with the appropriate purpose from the portrayed person (Article 19) The prohibition to change the name of the Author, the Work, the title alteration and the supporting title of the work. (Article 24)L Source : Data Processed from Articles of Auteurswet 1912 Stb. No. 600 and Act No. 6 of 1982. Matrix 9 Auteurswet 1912 Stb. No. 600 norms transplant into Act No. 6 of 1982 (Norms regarding registration system of Copyright) Regulated Material Registration system of Copyright Auteurswet 1912 Act 6/1982 Adhere the negative declarative registration system, Copyright of someone on his own work has already appeared with the success of the Work in producing one work with no other formality like the registration. Adhere the negative declarative registration system. The Work registration in the general list of the Creation does not mean as the legitimation on the substance, the meaning or the form of the creation listed. (Article 30) Source : Data Processed from Articles of Auteurswet 1912 Stb. No. 600 and Act No. 6 of 1982. The Registration system adhered both by Auteurswet 1912 Stb Number 600 or the Act number 6 of 1982 is the negative declarative system. The difference in that the Act number 6 of 1982 regulated clearly about the provision contained in Article 30. But this provision 154 was actually redundant, because that kind of attachment of that redaction, in reality did not give any good benefit juridically or practically. The person who register and the person who do not register shall have similar treatment in front of the law. Even though one person registered his right, but if there was another person who can prove otherwise, then the person who register his right, would have his right aborted. Matrix 10 Auteurswet 1912 Stb. No. 600 norms transplant into Act No. 6 of 1982 (Norms regarding Criminal Charges) Regulated Material Criminal Charges Source : Auteurswet 1912 Act 6/1982 The offense is the crime on The offense is the crime on complaint. The crimes on complaint. The crime shall copyright shall not be only be sued except on the charged unless on the complaint from Copyright complaint of the Author or Holder (Article 45) one authorized person to o Copyright infringement shall the action to defend the right. be sued with penalty of 3 years Or if there are two persons or imprisonment and fine at most more who have authority on Rp. 5.000.000,-. it, the complaint shall be To publish, show off or sell to done by them (Article 34) public a creation of criminal To violate someone’s infringement shall be charged Copyright at most Rp. 5000,- with 9 months imprisonment (Article 31). or fine at most Rp. 5.000.000,To publish or sell to public . one work which was known To violate the provision of as a violation on someone’s Copyright on a portrait, shall copyright, shall be fined at be charged with a 6 months most Rp. 2000,- (Article 32) imprisonment or fine at most To publically perform or Rp. 500.000,- (Article 44). publish a portrait with no right shall be fined at most 200 (Article 35, infringement offense) Data Processed from Articles of Auteurswet 1912 Stb. No. 600 and Act No. 6 of 1982. The Criminal provision contained in both Acts, principally had the same substances. There was no meaningful difference except on the adjustment on the amount of the former fine which still referred to the currency of that time. Even if there was a basic difference was on the 155 crime charged on the subject of the criminal offenders that was the imprisonment. In auteurswet 1912 Stb number 600 the charges was more human because it was just a fine. For an economic criminal action such as copyright infringement, the fine penalty was enough to be conducted. But nowadays, the copyright infringement has already reached a place to enrich people without paying attention to the right and purpose of the Author and Right Holder, then, it is now appropriate if the offender charged with imprisonment. Matrix 11 Auteurswet 1912 Stb. No. 600 norms transplant into Act No. 6 of 1982 (Norms regarding Civil charges) Regulated Material Civil Charges Auteurswet 1912 Act 6/1982 Civil charges shall be able to conduct by the Author or one of the Authors if the work created together. (Article 26) Civil charges on an unlawful action shall be conducted by the Author (vide Article 1365 book of Civil Law (Article 27)) The copyright gave an authority to confiscate announced items which contradicted with the copyright and also the duplication without consent and also able to sue the item as his or sue to make the work or itme to be abolished or un-used. The judge shall be able tom order conduct a compensation to the Author. That civil charges shall not decrease the criminal charges (Article 28). The civil charges shall be done on moral right infringement (Article 41). The copyright shall provide the right to confiscate the announced itemns which is contradicted with the copyright and un-allowed duplication and able to sue the hand-over of the item to be his or to charge the item to be abolished or tampered to become unused. The compensation charges shall not decrease the criminal charges on the Copyright infringement ( Article 42) Source : Data Processed from Articles of Auteurswet 1912 Stb. No. 600 and Act No. 6 of 1982. There is no criticize that can be said on the provision of this civil charges unless with a sentence that the transplantation on this Article was conducted flatly and wholly by the legislator. 156 If we pay attention on those explanations, it can be assured that the forming of Act number 6 of 1982 as an act of national legal product was not fully referred to the philosophical value of Pancasila. Whereas the desire of the society of Indonesia was very clear to replace the Auteurswet 1912 Stb number 600 because the Auteurswet 1912 was not appropriate with the legal need and goal of Indonesian society. The national legal goal must be read in the context of Republic Indonesia’s future goal. The goal with the meaning of hope or desire which formatted in the world of “idea” was formulated in the ideological basic and the philosophy of Indonesia that is Pancasila. The legal need of the society in the field of Copyright that moment was to push the creativity of the Creator to grow and develop well. To push for the sake of the better life in intelligence of the nation through the protection of copyright in science and the acceleration of the widening of the result of the culture. Whereas the national future goal with this new copyright was hoped to fulfill the national idealism that was to arrange an appropriate regulation with the philosophical basis of Pancasila and the juridical basis of the Constitution of 1945 and operational basis formulated in the state policy, which was TAP MPR No. IV/MPR/1978. Because of that, Auteurswet 1912 Number 600 was stated to be revoked. The history of the birth of the Act number 6 of 1982 was stained by various situation and condition, starting with the amount of copyright infringement until a political situation (law) which was not siding with the purpose of the Author. The validity period of Auteurswet 1912 Stb number 600 was marked with the amount of the infringement in book copyright. Actually since the beginning of the independence, Indonesia should have arranged its own regulation which referred to Pancasila and the Constitution of 1945 as the reference in formulating the national regulation. Even though in the era of President Soekarno was stained with political fluctuation and various challenge from in or outside the nation which still discussed about the existence of the independence of Indonesia in the era of President Soekarno had been established the Presidential Decree Number 107 of 1958 regarding the National Legal Development Institution. The reason to publish the Presidential Decree was mentioned that because in the time of colonialism, the Indonesia legal system was having a complicated deflection and all was done by the Colonial Government to fulfill the need of the government and the colonialist. In the practice, the Colonial Government with discriminative legal policy that was to divide 157 Indonesian society into groups and to each group was enacted its own law, caused the discriminative practice in law enforcement was getting worse. But on the other side, the government of Indonesia post independence was not also creating the new legal norms. Because of that, the legal norms of the Dutch Colonial still enforced. It was hoped in the transition period a review of the Acts of the Dutch Colonial could be conducted systematically to fulfill the national legal goal that was a regulation which was rooted from the Pancasila and the Constitution of 1945. It was realized also by the Government of Indonesia, that the alteration of the Colonial regulation could not be conducted all in once but was probably can be done step by step. It was also necessary to divide the enforced law with the outdated law both written in foreign language (Dutch) or in Bahasa Indonesia. The existed legal review and the new process of the making of the law which was planned systematically in order to build a planned legal system became a very strong reason of the government that time to build an independent institution which was called as the National Legal Development Institution.111 Although on the following days this National Legal Development Institution altered into the National Legal Development Agency. That alteration was poured in the Presidential Decree number 44 and 45 of 1974. The validity period of Auteurswet 1912 Stb Number 600 until the beginning of the independence, and continued 37 years after the independence both the National Legal Development Institution and the National Legal Development Agency had tried to arrange its own Copyright law which was rooted on the Pancasila and Constitution of 1945 to replace the regulation from the legal products of the Dutch Colonialism. This national legal system has been formulated in a seminar held by the National Legal Development Agency on 26 until 30 March 1979 which concluded that the national legal system itself consisted of the reflection of the values of Pancasila in the regulation and it made Pancasila and the Constitution of 1945 became the national legal basis. The national legal system must be appropriate with the legal need and consciousness of Indonesian society with the function as a tool to take care of the society. In formulating the national legal system must refer to principles attached in the political line poured in 111 See more the preamble of Presidential Decree of Republic of Indonesia Number 107 of 1958 regarding the National Legal Development Institution on 30 May 1958 in J.C.T Simorangkir, Serba- Serbi LPHN/BPHN, Binacipta, Jakarta, 1980. P. 25 158 the outline of the state policy which that time was enacted in TAP MPR Number IV/MPR/1978 which consisted of: 1. The Utility principle 2. The Togetherness and family principle 3. The Democracy principle 4. The Justice and prevalent principle 5. The livelihood and balance principle 6. The Legal consciousness principle 7. The self confidence principle These principles were the reflection of the values of the spirit of Indonesian Nation which was implicated in Pancasila which could be made as the basis to make the Indonesian rule of law and also could become a reference or a guide to openly test each born legal products. From the seminar, it can also be concluded that in formulating the law, the legislator need to accurately and smartly point the values of Pancasila as the basis of the normative provision contained in the law. With that, all of the law both in Acts or in implementing regulation must not contain values which are contradicting the Pancasila. By other words, the reflection of the values of Pancasila in the law was the substance in formulating the national legal system. The national law also directed in written form, this was meant to create a legal order and certainty although the unwritten law was still part of the national legal system. And the policy to unify the law must pay attention to the legal consciousness of the society. 112 The legal consciousness of the society was also have to be a political consciousness, the consciousness to celebrate a country and a consciousness of the political legal choices based from the values of the original paradigmatic value of Indonesian culture and society. At last it can be understood that the Act number 6 of 1982 which outline was the result of the transplantation of Auteurswet 1912 Stb number 600 could not run well in the process of the legal enforcement of copyright law as planned. In its journey in 5 years, the piracy of copyright was never been worse. Even in 1982 – 1987 Indonesia was listed as the second piracy country after China. The pressure from the internationals appeared one by one. The pressure was from the United States of America so that Indonesia respect and appreciate the copyright especially the foreign copyrighted works. 112 The Conclusion of national legal seminar the IV held by National Legal Development Agency- Department of Justice, Jakarta 26 – 30 March 1979 in Ibid, p. 327 - 320 159 These pressure and reasons were becoming the consideration to alter the Copyright Law number 6 of 1982. The information and data and also the writings from academicians have arrived at one conclusion that the rate of the violation and piracy of copyright was already at the worst point. The damage effect was not only to the Authors and producers but also to the life of society sectors as the consumers. The damage effect was about the worsen of the legal culture which was awaken because of the weakness of legal enforcement. And also the loss which was caused economically on the Authors, the person who was entitled to the right who also has influence in the publishing industry, the recording industry and the film industry. In the connection with those things mentioned, Charles Gielen prevailed that: The report from the crowd commonly and especially the Authors and all kinds of professional association who have interests in Copyright in the field of song or music, books and publication, film and video recording and computer, reveal that the violation of Copyright has increased and now has reached a dangerous rate that is decreasing the passion to create. In a wider definition, a copyright infringement would also endanger the basis of common social life. Of course the increasing of the violation was influenced by many factors. The limited definition from the crowd of the meaning and function of copyright, the attitude and passion to get a benefit from the business easily , plus the difference of the translation and the action from the legal enforcement official in facing the copyright violation was the factors that must be paid attention to. 113 Gielen’s statement above created a belief on industrial countries who were bothered economically as the effect or the Copyright piracy in Indonesia. This events made the President of United States and European Commission and the World Intellectual Property Right Organization (WIPO) in January 1987 under the coordination of Arpad Boqsch (General Director of WIPO) to visit Indonesia to discuss the steps to alter the intellectual property right regulation including Copyright law. 113 Charles Gielen, Undang-Undang Hak Cipta Baru Indonesia, Implikasi Untuk Penanaman Modal Asing, Paper on the Intellectual property Rights Seminar, Law Faculty USU, Medan, 10 january 1989 p. 6 – 7. 160 The United States has applied a one sided sanction to Indonesia that was to apply the trade policy as the tool to press the Indonesian government to fix yhe enforcement system of Intellectual property Right in Indonesia. The improvement expected by the United States of America was not only from the legal enforcement, but also in the substance of the regulation. Even according to Gielen 114 the Government of United States in 1986, announced their intention to reconsider the preferential status of Indonesia based on Generalized System of Preference (GSP) (based on the trade and tariff law of 1984). Indonesia was given a chance until 1 March 1987 to alter the existed Copyright Law or to establish new Act. The time period was prolonged until 1 October 1987. It turned out that until 1 October 1987, Indonesia had finished to arrange its Copyright Law which was enacted on 19 September1987. Indonesia, which had already received GSP status in 1980 and continued in 1985 had the right based on the import duty system to get a preference to be freed from import duty in the matter of the export to United States from items or goods in maximum range of price US $ 28 million. Even though this is not a big amount, if calculated in the scale of international trade, but the withdrawal of the preference of course would hurt Indonesian economy and prevent Indonesia from getting a bigger export volume to the United States of America. 115 Based on the regulation of the board of the European Commission Number 2641/84 the steps of the trade policy can be run to the third counties on the basis of unhealthy trade practices in those countries. Based on this regulation the International Federation of Phonogram and Videograms Producer (IFPI) propose a complaint to the European Commission. This commission stated that there were enough evidences to begin an investigation.116 On that violation and piracy of many foreign intellectual property right in Indonesia, caused the appearance of a suspicion from the internationals that Indonesia did not give any protection on phonogram reproduction, cinematography, computer program, and another possessed by foreign Author. That incapability was marked by the amount of the piracy of phonogram in Indonesia. While it happened, the European Commission decided to give chance to 114 Ibid Official Journal, 20 September 1984, L252 in Charles Gielen Ibid P.9 116 Ibid, p. 9 115 161 Indonesia to improve the system of law enforcement in the field of Intellectual until 29 February 1988. The International pressure, especially from the government of the United States, has caused the establishment of President Soeharto’s Decree on 30 July 1986 to create a “Special Work Team to search for the solution to the problem of the enforcement of copyright law, trade name and trade mark and the creation of a patent law”. This team had already implemented its function as useful as possible because in the beginning of 1987 the alteration design had been published. This design had been delivered to the House of Representative on June and enacted as an Act on 9 September 1987 and enforced since 19 September 1987. Remembering that Indonesia had made the alteration on the Act number 6 of 1982 and let the European Commission know that Indonesia was ready to discuss a way out in order to provide similar protection on the foreign works and the works of Indonesian citizen. 117 Which means, even though Indonesia had altered its own Copyright law, the international pressure would keep on going as long the violations on the foreign intellectual property is still found in the law enforcement. D. The Period of Copyright Law Number 7 of 1987 (1987 – 1997) After 5 years of the establishment of the Copyright Law of 1982, that was between 1982 – 1982, it turned out that there were a lot of things happened in the enforcement practice of the act. The influence of the acceleration of computer technology and information had changed the cultural behavior and legal behavior of the society, which in turn also influenced the aspect of Copyright Law enforcement. The alteration and development of the society was not able to be anticipated by the Copyright law number 6 of 1982. There was a consideration that the criminal sanction applied in the Act number 6 of 1982 was too low or the offense which character was categorized as offense on complaint made the pirate or the copyright offender became free since the certainty of the Author or the Copyright Holder would not do the complaint in the law violation they did.118 117 Decree of 23 November 1987, Official Journal on 25 November 1987, L335, in Ibid. 118 The seller of the pirated VCD/DVD had the belief that the Author or producer would not do the complaint because beside they would not know the pace of the event of the piracy also happened in various locations which were hard to be detected, so that the complaint was not possible to be done especially the pirated DVDs and VCDs were belonged to the foreign Author and Producers. It was not possible the Americans or 162 Beside that, there were 4 (four) legal consideration which became the reason to make alteration on the Act Number 6 of 1982 as poured in the preamble part consideration of the Act number 7 of 1987 regarding the Alteration of the Act number 6 of 1982 of Copyright: 1. Legal protection is given on the Copyright which was meant as an effort for realization of a better vibe on the growth and passion of the creation in the field of science, art, and literary. 2. In the middle of the process of the accelerated national development, especially in science, art and literary, the copyright infringement has also developed, especially in the criminal action as piracy. 3. The Copyright infringement has arrived in a dangerous rate and could damage the system of society life in common and especially the passion to create. 4. To anticipate and stop the copyright infringement, it was necessary to alter and perfected some provisions in the Act number 6 of 1982 regarding the Copyright. 119 Referred to the preamble of the act above, it can be understood that this preamble was far away from the philosophical values. The considerations were given more on the practical consideration. The vibe of the idea, goal, or thoughts which were connected with the philosophical basis of Pancasila and the national goal as contained in the opening of the Constitution of 1945 was almost cannot be found in that preamble above. See the explanation regarding the background of the alteration of the Act number 6 of 1982 was only based on the desire to provide legal protection on the copyright (probably to the Author). The target was very pragmatist. Another consideration used was that this alteration triggered by the existence of the of the activity to violate the Copyright in criminal action of piracy which had arrived in a dangerous rate and it was seen as an action that damage the social life system in common and the passion to create. Practice and very pragmatist considerations showed the simplicity the thinking pattern Indians did the complaint at the Police Department of Medan Baru for instance. This kind of event is what triggered a massive piracy on phonogram and cinematography. Moreover, in the practice of piracy in both creations has been ingrained in almost all places in Indonesia. In various report, 90% of the VCDs and DVDs circulated in Indonesian market were results of piracy. For more see Tempo Newspaper 8 March 2003. 119 The preamble of the Indonesian Act number 7 of 1987 regarding the Alteration on the Act number 6 of 1982 regarding Copyright part consideration item a, b, c, and d. 163 developed in the legislator institution that time. Ideologistphilosophical considerations which referred to the national legal goal almost cannot be found in the Act’s preamble. Also the political pressure factors and international legal policy almost cannot be found in the basis of the consideration because the political steps which should be poured in preamble as the political basis in national legislation were also cannot be found. That consideration was necessary to see the legal policy outline in anticipating the Indonesian association in International life in globalization era which was meant as a trade era which no longer limited by national walls of a country. The globalization demand was felt by the Indonesian government at the time the pressure from Internationals to alter the Act number 6 of 1982. There was a dishonesty of the government and the legislator institution in arranging the Act number 7 of 1987. International pressure on Indonesia was hidden and wrapped so tidy so that the alteration of the Act number 6 of 1982 was seen as an appropriate alteration. That was why in the preamble of the Act a pragmatist and practical considerations were the ones that showed up and put aside the ideological considerations. The steps like that would also gave effect in the weakening of nationalism vigor and the vigor to fight and hold on in the pressure of global economic powered by practical and pragmatist steps like that would be brought to the direction of capitalist country’s economic development, as seen by Fukuyama. 120 Actually since the beginning, the founder of this nation hoped that this country was built on the basis of Pancasila which contain the religious belief inside it. What was actually hinted by the founder of the nation was to anticipate both ideology predicted Fukuyama as the holder that were capitalist and liberal democracy ideology. The winning of both ideologies by Fukuyama was predicted would still survived until the next century because both ideology were based on very elements. Maybe that was caused the Indonesian choice when arranging the Act number 7 of 1987. The consideration based on practical, pragmatist and rational consideration. On the other side, 120 Fukuyama in his writing predicted that this world would end with the winning from liberal and capitalist democracy. The democracy has influenced so much political thought in the whole world and given birth hundreds or even thousands books which spoken and considered as the only form of political ideology which is the most ideal in the whole world. While capitalism even though caused a lot of controversy and pro-contra but still was the ideology which attracted a lot of people. Capitalism promised economic welfare and political justice which can be reached by human through hardworking and self-ability in maximum. See more Francis Fukuyama, The End of History and The Lost Man, Penguin Books, London, 1992, p. 69. 164 Pancasila was not only put the consideration and the political choice based on pragmatist, practical, and rational choices. Since the beginning, the founder of the nation admitted that the Indonesian independence was realized not based on rational predictions but based on irrational predictions. That was why in the opening of the Constitution of 1945 it was asserted that Indonesian independence was realized on the blessing of the only one God. If the rational consideration used by Indonesia, it was not possible Indonesia reached its independence with the bamboo weapon against more modern weapons used by the colonialist (Netherlands, Japan, and the alliance). It was also not possible Indonesia achieved its independence if the diplomacy struggle was just done by some educated people compared to the opposite side who had better education that time. Once more, that proved that there were irrational considerations in the political choices. The choice on the national country for example, which was based on the difference on tribes, or groups of the society which became the basis of civil society, religion and belief which was necessary as a target to achieve the goal of the history. 121 For the case in Indoneisa, the elements of religion and belief borrowed the thought of Fukuma should also made as the target to achieve the legal future goal. the element of religion and belief would still dominate the journey of the civilization of Indonesia, even though in the end capitalism would take control but the achievement there would take a long time. If since the beginning in many process of the law making, legislation policy in this country made Pancasila as the basis of the ideology, it can be predicted that capitalism would be extinct with a new alteration. There was a belief that the history moved in circle pattern, if the religion factor and the belief could not be erased, then the sovereignty (politic and ideology) must be altered. Also in liberal democracy and capitalist ideology would fall down since no one could make sure that the liberal democracy can make people to rule in even, or became leaders, and capitalist ideology could make people rich or poor. Both ideology could not make people to be in a same spot to 121 Fukuyama, Ibid . Also compare it with Ian Adams, Ideologi Politik Mutakhir Konsep, Ragam, Kritik dan Masa Depannya, Qalam, Yogyakarta, 2004, p. 459 by citing Bell, Ian Adams concluded that Bell and Fukuyama, both showed that the West with welfare state genre and mixture economic system has achieved the end of ideological era and enter the last era of history which is like freeing the human from frustration and realizing the aspiration to get the living standard with the choice of capitalist ideology and liberal democracy which by Ian Adams called as triumplasme ideology (the winner’s ideology) 165 enjoy happiness. People would not be in the same position to be provided by justice. People could not all be smart or be appreciated. When the most support achieved by someone or a group of people, then he is going to be the winner, but the winner shall never be appointed as the winner by the losing one. Here was when the new phase of the history began, moved in circulation.122 In legal perspective, Indonesian law which would be arranged was the law based on the spirit contained in Pancasila ideology. It was not the law which directed the society to become capitalist society with liberal democracy political system. Pancasila ideology is indeed not rational. It was not like liberal democracy ideology and capitalist ideology which counted on rationality. Rational always rooted on brain, but irrational rooted on mind. The world was believed not only run based on considerations of the brain but also with the deepest mind. In liberal democracy ideology and capitalist political choice was not based on the mind, but on the brain.123 This choice of ideology is very important because if the ideology was chosen based on the brain’s consideration, it can be ascertained that human has entered a very dangerous spot because the effect appeared after that would be a “bad” ideology. If this bad ideology was believed by a leader for the continuance of the human civilization forth, what would be happened is chaos. Because of that, it is wise if the laws o the legislations arranged must based on the right choice of ideology. And for the case in Indonesia, there is no other choice except Pancasila ideology. It is wise if the legislators open their mind and heart to understand clearly the relation between ideology and the legal policy run by the leader. It is necessary so that since the beginning it can be realized what kind of norm shall be formulated in the legislation formulated as national legal policy. So, the process of the making of Act number 7 of 1987 should not be based on the considerations attached in the preamble of the Act above. It was not also to tightening the legal sanction in the infringement or the criminal action in copyright piracy. The pressure to strengthen the legal sanction on criminal action actually had let down 122 The description was described in Al-Quran. That the sovereignty would be altered, nothing is eternal, and nothing last forever except The God that is Allah. That was put by the founder of the nation as ideological basis that was placed in the first principle which is the spirit of the other four principles. 123 The appearance of this ideology was begun since the renaissance which was based on the rationalism ideology. 166 the value and dignity of the nation. The law seemed like to need a great sanction to be obeyed.124 We can see how the choice of alteration made in the Act Number 7 of 1987, at the beginning the Act put the offense of copyright infringement as offense on complaint, but in the Act number 7 of 1987 it was altered to be a regular offense. That means by altering the provision to be a regular offense the law enforcer would become more capable to do the investigation without waiting on the complaint from the Author or the Copyright Holder. The alteration on the status of the offense was not separated with the demand from the internationals which has the background of capitalist countries, because of that, such alteration had the support from the Western Countries especially United States of America. Their reason was to make the society of Indonesia understand and respect the rights of another people, but actually that was not the intention of the Westerns, their intention was to make Indonesian people become more civilized with the offense alteration. Probably with a greater sanction, Indonesian could obey more. This liberal ideology was getting real when the time period of copyright which was as long as the author lives plus 25 years after the death of the Author, in the Act number 7 of 1987 the time period was prolonged until 50 years after the death of the Author. This time period was finally put back just how the Auteurswet 1912 Stb Number 600 put it. The long time period caused the copyright was more far away from applying its social function. The alteration on time period of the of the copyright ownership was actually based on the demand from internationals, because most of the capitalist country in the national legislation has limited the copyright time period in the life span of the creator plus 50 years after the Author’s death. The choice of national copyright legislator to not have the courage to be different from those capitalist countries was because of the political pressure factor which haunted behind the alteration process of the national copyright law, even though the thing was never could be explained normatively. 124 Just like childhood story, elder used to describe the fear to the police. The crying children would be quiet right after the parents told them that the police would be there soon. Threats like these were the threats that only be able to be given to the children who had no knowledge or awareness regarding the meaning of life, precious meaning regarding our appreciation to people’s effort. There was something missing in this nation, moral awareness, cultural awareness, religious awareness but that did not mean the law must placed them in the childhood position. 167 Some official explanation by the government in the information in front of the House of Representative Assembly regarding the design of the act of the alteration of the Act number 6 of 1982, was not also explain the political pressure which became one of the reason to alter the copyright law, except the governments explanation regarding the alteration of this act based on the design of alteration of the Act number 6 of 1982 regarding Copyright, which was mentioned by the President to the House of Representatives though the official letter Number R-03/PU/III/1987 on 25 March 1987. Next, it was explained that the 5 years experience of the enforcement of the Act Number 6 of 1982 confined many experience, and it was admitted by the government as something that was worth to be made as a lesson. It was also admitted that the national Copyright Law was sourced from foreign law. 125 Even though the regulation regarding Copyright has known by Indonesian society for 75 years, (70 years of the enforcement of Auteurswet, 5 years of the enforcement of Act number 6 of 1982) the government still stated that this field of law is still relatively new. It was not clear the new criteria used by the Government. 126 But, there was a hope that was intended to be achieved by the Government by altering this Act that was to create a better vibe on the copyright protection than the previous time. 125 It had already 5 years, since the Act Number 6 of 1982 re garding Copyright was verified on 12 April 1982, the Indonesian had the set of Laws that regulate the legal protection on their work in the field of Science, art, and literary. All that time, there was enough experience to enrich the knowledge of life in those fields. Various things appeared and grew the awareness of the nation regarding the weakness which had to be fixed for the sake of the future. So far, the government considered the experience as a very useful lesson. Even though it had to be admitted that the concept of copyright as individual right with exclusive character and has no form , and the regulation inside the legal system , was indeed studies from the foreign law. In this connection, Everyone should have the same opinion with the government regarding the respect to individual or the right attached which was actually the characteristic of Indonesian. But then the right was spread clearly in positive legal system especially in the field of economy, it was indeed a relatively new concept for the society of Indonesia. 126 It is still fresh in our memory, how big our belief in arranging the design of Copyright law was, and agreed by the House of Representatives regarding the necessity to grow the attitude to respect and appreciate a work in the field of science, art and literary. These are all indeed without no consideration, and also without any basis. The respect and the appreciation on a work in science, art and literary was not only regarding the admission of one’s individual right on his work. It was also not only the admission on the owner’s right or the copyright holder to enjoy the economic benefit in certain meaning on his right. 168 The stimulation of the development of the copyrighted works which were born by the people of Indonesia was also the main desire of the Government in amending the Act number 6 of 1982. Especially in certain fields, such as on the computer program that was new that time as a knowledge or science. Even though not all the issues of the computer program protection was for Indonesia, but as a nation that depend strongly on industrial countries like America, like it or not, Indonesia had to accept the offer from America to put in the aspect of computer program as a part of the works that has to be protected. 127 The creation of this kind of vibe was what has desired to be realized, developed, and utilized. In order to apply the national development, that kind of vibe was really necessary. Because, only by that the growth and development of the passion to create in the field of science, art and literary can be counted on. It has already so often the opinion regarding the importance on the science and technology for the life of a nation and the future to be heard. Also in the field of socialculture, it has been the goal to realize the strong Indonesian characteristic in the middle of the international countries’ life which also grow and develop. In this connection, it was hoped that the growth of the development on art and literary in Indonesia in the field of song and music, movie and literary writings, the art of dance, the art of drama, the art of painting, the art of carving and the other, to go better. With the background of that thinking, the Act number 6 of 1982 was arranged together. Now, the question appeared is how about the experience all along and what problems were in the background of the proposed design of the Act regarding the Alteration of the Act number 6 of 1982. As we know, both the report or the news from press, since these few years, it has been heard more and more the Copyright violation. The background of all those was that basically it was actually for the purpose to achieve financial benefit in no time by disobeying the interest of the Copyright Holder. The effect on the violation was so bad on the living system of the nation in economy and law fields. in the field of socio-culture, the effect appeared on the piracy was various. For the offender of the pirate, this continuing event without any action, would cause the attitude that piracy is a common thing and no longer is 127 Moreover, the steps to renew the law which was done by arranging the Act Number 6 of 1982, consciously was directed especially to the effort to create a vibe that can stimulate Indonesian people to create works in those fields. This was the vibe that was worked on through the admission on the right and also the providing of the legal protection system on the right. 169 an unlawful thing. For the Authors, the event grew the apathetic attitude and reduced the passion of the Author. For the society as the consumer, the growth of attitude which no longer see the necessity to question if the work was the result of violation of law or not. The more people disobey what is right or wrong, what is legit or not, even though our country is a country with law basis. People questioned if the culture and attitude of our nation is already that bad regarding the appreciation of a work in the field of science, art and literary. The observation to that kind of condition turned out to have a great effect to our international relation. By concerning the resulted damage and troubles, the Government on 30 July 1986 had formed and delegated a working team to: First : to study and finish various problems connected with the application of the legislation in the field of science, trade mark and company mark. Second : to accelerate the settlement of the arrangement of the design of the legislation regarding the patent. The working team led by the Young Minister/ Cabinet Secretary consisted of some senior official member from the Department of Justice, Department of Industry and Trade, Department of information, Agency for the Assessment and Application of Technology, and Indonesian Institutes of Science. Since the forming, the priority to handle was given to the settlement of various problems in the field of Copyright. Some meetings was held with the Chamber of Trade and Indonesian Industry and related Associations which had the interest with Copyright. The goal was to achieve more clearly the real condition, and also the data, suggestion, or other necessary things. Those associations were: In the field of music : 1. Community of Creator Artist Recording Musician of Indonesia (PAPPRI) 2. Indonesian Recording Industry Association (ASI-RI) 3. Indonesian National Recorder Association (APNI) In the field of Books : 1. The league of Indonesian Publisher (IKAPI) 170 In the field of movies 2. Indonesian Author Association (AKSARA) 1. Indonesian Film Company Association (PPFI) Recording Video Entrepreneur Association (GABSIREVI) : 2. In Computer Program Field : 1. National Information Company Association (APNI) 2. Indonesian Computer User League (IPKIN) In the field of movie, consultation and suggestions were accepted from the Associations of Chinese movies and EuropeAmerica, also Video Recording Industry Association (ASIREVI). Also in the field of computer program, consultation regarding the effect of the possibility of the legal protection providing to the computer program on the price of the computer program (especially on Personal Computer/PC), it had also being consulted with the Indonesian Computer Industry Association (AIKI). Beside that, the Consultation meeting had also been held by the team with the experts in this field. All then were reviewed which finally resulted this design of Legislation. To complete the description regarding the condition happened, the working team led by the young Ministry/ Cabinet Secretary conveyed the conclusion achieved from the meetings with the Associations related to the Copyright such as: First : the violation on copyright especially piracy, by the associations had been judged to reach a very dangerous rate that endangered the creativity to create. Second : the conviction in the Act number 6 of 1982 regarding Copyright was too easy and so was the application. This thing made the Act no longer able to prevent criminal action in Copyright piracy. Third : lack of coordination and agreement, attitude, and action between the law enforcers in facing the problems in copyright infringement. Fourth : lack of understanding regarding the meaning and function of Copyright and the provisions of Copyright in the common society and even in the Authors society especially. 171 In detail, it was represented further regarding some quantitative data that reported by the Associations to the government. For example the case in the field of music, songs and movies, those were the fields that suffered the most because the criminal act of piracy. In the field of music and song, the piracy was on to the works of both Indonesian Author and Foreign Author. The last one, especially are the western songs. According to ASIRI, the damage suffered by cassette recording company contained music of Indonesian songs because of the piracy, in whole, reached Rp. 900 million per month or approximately 10 billion rupiahs per year. Especially regarding music and foreign songs, the reaction then came from outside of the country. In the field of the movie, PPFI, GABSI, REVI, or ASIREVI, all stated that the piracy of national or imported movies, including video recording, kept accelerating. If in 1983 the pirated movie was listed for 30 movies, then in 1985 – 1986, 90% of all the movies even pirated in video before officially published. Same event happened in the field of books. Even though in amount or value it was not as big as the damage in the field of music or songs, but both IKAPI and AKSARA really suggested that the action to stop the violation on Copyright should soon be taken. Also in the effort to grow computer industry more in the country, the computer society represented by APNI (trade service), IPKIN (user) or AIKI (maker), asked and suggested so that computer program could clearly stated as protected copyrighted work. The suggestion accepted by the Government not only in the scope of things related to the infringement and piracy and also the thought or suggestions to prevent it. The problem was indeed a main problem. But beside that, in order in the effort to accelerate the regulation and protection of the Copyright, many thoughts were accepted regarding the possibility for the perfection many provisions in the Act number 6 of 1982. It was not only on the conviction, but also to reach the scope of the Act enactment, the time period of the protection, and etcetera. Further explanation was necessary regarding the problem in proportional, especially in the connection with many view, question or sometime doubt that the taken steps right now caused by international pressures. In this thing, we are all agreed that as a society with nation, independence, and sovereignty, decision regarding what is best for us must be taken by the nation itself, not because of the pressure. So far, the existence of some alteration on provisions that have effects both to outside the nation or to foreign Copyright Holders was what caused the impression. One of the future goal in the nation life as asserted in the 172 Opening of the Constitution of 1945 was to take part in implementing the world order which based on the independence, eternal peace, and social justice. Also side by side with the goal, the legal system created not only should be able to reflect aspiration, need, and the interest of Indonesia, but also to always directed to be in line with the aspiration, need, and interest of other nations. As legal principle, one did not want to be disadvantaged because one did not put anyone in disadvantage. Since one did not pun anyone in disadvantage, no one would like to be put in disadvantage. All believe that with the similarity and balance in life between nations, then, the world order based on independence, eternal peace and social justice shall be realized. Indonesian nation clearly wanted to be and to settle as a respected and responsible world citizen in realizing that kind of world order. In the set of the similarity and this balance too, other things with a necessity in explanation was the existence of international convention in Copyright protection. In connection between nations, this convention was the one which essence was the rendezvous point of the connection of legal interest of various nations and countries in the world. Because of that, on time Indonesia should consider its part in the convention because of the national reason as well as the relationship between nations, or in the acceleration of cooperation in trade, economy, and politic, it was if in certain limits, in line with the national need or interest. It is also the time to consider some provisions in the convention that accepted in the national legislation of Indonesia. And the problem regarding when Indonesia will take part in the Convention, need to be studied and learned deeply and carefully. In this connection, the Government conveyed the alteration to the perfection about some provisions in the Act number 6 of 1982. There are some important parts of the Act number 6 of 1982 that are in need of alteration: First, the matter of the criminal; Second, the scope of the Act; Third, the time period of the copyright enforcement; Fourth, the relationship between Country and Copyright Holder. Beside those main things, another alteration which basically was to perfected the redaction in order to clarify the provision, or to adjust related to the main alterations. If we paid attention on those four points of alteration, they did not reflect the national legal goal development which is based on Pancasila ideology. Those for points of alteration as explained before were mainly because of the pragmatist consideration for the practice 173 interest as the requirement to answer the demands from Western Countries that based on capitalist ideology. There were four important parts in the alteration of Act number 6 of 1982 to the Act number 7 of 1982. This alteration from Copyright Law number 6 of 1982 to the Act number 7 of 1987 if presented in matrix form, shall be seen like this: Matrix 12 Alteration from the Act number 6 of 1982 to the Act number 7 of In Criminal Aspect Altered Substance Regarding Criminal action Source : Material of Articles Act No. 6/1982 Penalty: Imprisonment at most 3 years and fine at most 5 million (Article 44 paragraph 1) Imprisonment at most nine months and fine at most 5 million (Article 44 paragraph 2) Imprisonment at most 6 months and fine at most Rp. 500.000 (Article 44 paragraph 3) Altered Material poured in Articles in Act number 7 of 1987 Penalty: Imprisonment at most 7 years and fine at most 100 million (Article 44 paragraph 1) Imprisonment at most 3 years and fine at most 25 million (Article 44 paragraph 2) Imprisonment at most 2 years and fine at most 15 million (Article 44 paragraph 3) Explanation From the aspect of the criminal, the legislator put forward the reason that the disloyalty of the society to the Act number 6 of 1982 was cause more on the minimum penalty on the criminal offender. Data processed by Saidin by comparing between the Act number 6 of 1982 with the Act number 7 of 1987. 174 The first field altered was regarding the criminal regulated in the Article 44 Act number 6 of 1982. The direction of the alteration was basically to harden the criminal penalty on the criminal action of Copyright violation. In the Copyright Law of 1982, the penalty as regulated in Article 1 was given with imprisonment at most 3 years and fine at most 5 million (Article 44 paragraph 1) altered to imprisonment at most 7 years and fine at most 100 million. As well as in Article 44 paragraph 2 was only threatened with imprisonment at most 3 years of fine at most 25 million.128 The following alteration was the penalty regulated in Article 44 paragraph 3, if the criminal was first threatened with imprisonment at most 6 months and fine at most Rp. 500.000 (Article 44 paragraph 3) then in the alteration of the Act, the penalty was accelerated to be at most 2 years and fine at most Rp. 15.000.000,The alteration from criminal to this worse, basically was meant as one of the effort to accelerate the ability of the law to tackle the Copyright infringement and to prevent the offender from committing again. That was the message implicated or hidden which then poured by the legislator in the Article regarding alteration of the penalty regulated by the Copyright Law. The legal policy to harden the penalty, showed the distance of philosophic understanding of the legislators at the legal culture of Indonesian society. Because at last even though the penalty had been harden, it could not be proven that it was also lower the copyright piracy or copyright violation. The legal culture of Indonesian society should be understood holistically not only viewed with bare eyes that the piracy behavior or copyright violation were only caused by the light penalty. Our observation since June 2012 until December 2012 proved that the copyright piracy especially in cinematography produced in VCD or DVD proved that a worse penalty did not stop the piracy activities or copyright violation. 129 There was a lost cultural understanding in the legislators to the legal behavior, 128 In Copyright Law of 1987, then set with imprisonment at most 7 years and fine at most Rp. 1.000.000.000,- Article 44 paragraph 1. 129 Every evening in June and December 2012 we watch the supplier of the pirated VCDs and DVDs in more than 20 stores operated in the edge of the road, in Dr. Mansyur streets, Drussalam Street, Setia Budi Street, Kapten Muslim Street, Titi Papan Street, Jamin Ginting Street, Krakatau Street, Sutomo Street, and almost in whole streets in Medan city untu=il in shopping center like Petisah Market, Sei Sikambing Market, Peringgan Market and the biggest market in marketing the pirated cinematography in Belawan city. Our done observation was strengthening our belief that with the high level of copyright violation as meant by the legislation, it did not change the behavior of the society who had the involvement in those activities. 175 economic behavior and socio-culture behavior in Indonesian society. If there was a cheaper price, the society would not but a more expensive stuff. It is not the time yet for Indonesian society to calculate the quality aspects especially when the bought stuff was giving satisfactory only on the first use. It is so seldom a consumer watch or reply the same VCD/DVD repeatedly. So the quality aspect did not become an important matter to the consumers. This fact would become a determinant factor why at last the consumer must but the pirated VCD/DVD even though it’s realized that the action was a criminal action or civically was an unlawful action. The choice of the legislator to accelerate the penalty was strengthening the assumption that to prevent the piracy of copyright violation, the most accurate step was to harden the penalty. Indonesian society as the subject of criminal offender, must be shadowed with a higher penalty to obey the law. A cultural phenomenon which was far from the real society would become the country’s responsibility to protect. The goal to protect the Indonesian society, to bring forward the general welfare was disobeyed when the legislator positioned the Indonesian society as a subject who needed to be scared off with the penalty. This assumption was strengthened with the next target which wanted to be achieved by the legislator in the Copyright violation, because beside those alterations meant to punish the offenders or the pirate, it was also meant to be a adjustment. Adjustment here, means the imprisonment, alteration from 3 years to at most 5 years, based on the consideration to fulfill the minimum standard of the imprisonment provision as contained in Article 12 paragraph 4A in the book of criminal law. As understood, based on that provision, the imprisonment can only be done to the suspect and defendant who did the criminal action and/or the trial or assistance in the criminal action in the matter of the criminal action is was threatened with 5 years imprisonment or more. Also the acceleration of maximum limit of the fine, based on consideration that the Copyright piracy, regarding a bigger money value. But by still giving freedom the judge to make decision with his belief, the design of this Act provided the penalty of imprisonment or fine both in cumulative or alternative. It proved that Indonesian society by the legislator has not placed as a legal subject who also need to be protected. By other words, the legislation disobeyed the philosophic basis of humanity which is in justice and civilized, every criminal provision should contain provision that humanized the human, not positioned the Indonesian society at the lower rate. That every criminal 176 offender must provided with a severe punishment, without seeing the factors around why people commit criminal action. The characteristic of the offence also altered from the offence on complaint to regular offence. The Alteration of the characteristic of this offence was also meant to make easier the investigator to soon implement legal action without receiving the complaints from the Authors and Copyright Holders as stated in matrix below. Matrix 13 Alteration of the Act number 6 of 1982 to the Act number 7 of 1987 Based on Criminal Classification Material in Altered Material Articles Act No. poured in Articles Explanation 6/1982 number 7 of 1987 Criminal Characteristic of Characteristic of Classification offence : offence: Offence in Regular offence complaint (Article 45) Source : Data processed by Saidin by comparing between the Act number 6 of 1982 with the Act number 7 of 1987. Altered Substance If observed carefully the provision contained in the Auteurswet 1912 Number 600 , the act still paced the criminal act on copyright as offence on complaint. With this alteration, the legal enforcer was asked to be act more proactively in limiting the copyright. There were some considerations which became the basis to make the alteration on the offence on complaint to be a regular offence, such as: 1) Based on experience, the damage caused from the existence of copyright infringement not only suffered by the Copyright Holder. The Country also did not achieve the income tax on the benefit achieved from the piracy. Beside that, without we realizing it, the social, legal, and economic order has been threatened. 2) The Copyright infringement, as an individual right, more certainly be classified as a regular offence on stealing, deprivation, and fraud or deception. The basis of the consideration used by the legislator that time was the offence on complaint, actually would be more certain if connected to the violation on the honor or dignity such as humiliation, 177 rape, and becoming not right if implicated on Copyright infringement which put more effect on economy, social, and legal order in general. The third problem connected with the alteration in this criminal was the addition of provision regarding the deprivation on the result of Copyright by the Country to be destroyed. The addition of this provision was meant to as good as possible to decrease the damage morally or economically by the Copyright Holder. By that, the result of the infringement did not just deprived. The work was basically not allowed to be traded and must be destroyed. The fourth which also connected, was the assertion on the existence of the Copyright Holder Right to propose the civil suit to the offender, without decreasing the right of the country to do the criminal charges. Beside the criminal affair, another part that needed alteration in the Act number 6 of 1982 was regarding the scope of the copyright. If at the beginning, based on the provision of Act number 6 of 1982 the protection to the foreigner’s copyright in Indonesia could only be protected if for when listed for the first time in Indonesia and the previous work announced in another country would not have any legal protection in Indonesia. But, in Act number 7 of 1987, the foreigner’s work would be protected in Indonesia if the foreigner’s country had a bilateral agreement in copyright protection with Indonesia and the country participated in multilateral protection in copyright protection and Indonesia also participated in it, as stated in matrix below. Matrix 14 Alteration Act number 6 of 1982 to the Act number 7 of 1987 Based on the scope of enforcement Altered Substance The Scope Source : The material Act No. 6/1982 The work of foreigners in Indonesia can obly be protected if protected for the first time in Indonesia Altered Material poured in the Articles Act number 7 of 1987 It shall be protected of the foreigner’s country possessed bilateral agreement in the field of copyright protection with Indonesia. Participated in multilateral agreement in the field of Copyright and Indonesia also participated in it. The Work which previously announced in another country would not be provided with legal protection in Indonesia. Data processed by Saidin by comparing between the Act number 6 of 1982 with the Act number 7 of 1987. 178 The reason that the legislators that time in conducting the alteration in providing legal protection to foreign copyrighted work was because before that time, the foreigner’s work would only be protected when announced for the first time in Indonesia. By that means, the work previously announced in another country, would not be provided with legal protection in Indonesia. This provision was difficult to implement. This alteration, however was directed to the providing of legal protection, if the Country of Copyright Holder: a. Have a bilateral agreement in Copyright Protection with Indonesia, or b. Participated in multilateral in Copyright protection, and Indonesia was also a member in it. But because of the participation in such multilateral agreement need a long time to be studied, and often must be followed with a substantive adjustment at the minimum standard set in the agreement, then the existence of bilateral agreement at least would be a bridge for both country to provide protection to each other. The hope of legislator with this alteration, was that Indonesia would be able to provide something in effort to harmonize the relationship between countries in this world especially in trade area. Matrix 15 The Alteration of Act Number 6 of 1982 to the Act Number 7 of 1987 Based on time period Altered Substance Time Period 1. Regarding the time period 2. Regarding the Application of the regulation The Material of Articles of Act Number 6 of 1982 The Copyright enforced as long as the Author lives plus 25 years after the Author’s death Article 26 Altered Material poured in the Articles in Act number 7 of 1987 Copyright on work: a. book, pamphlet, and all kinds of written works; b. dance art ( choreography); c. all kinds of arts such as paintings, crafting, and statues; d. batik art; e. song or music creation with or without text, and f. architectural works; enforced as long as the author lives plus 50 years after the Author’s death 179 The copyright or photography work or cinematograph y work also works made based on the similar working in 15 years calculated 15 years since announced for the first time (Article 27) Article 26 (1) Copyright on : a. performance work like musickarya pertunjukan seperti musik, karawitan , drama, dance, wayang, pantomime, and broadcasting works for example for media of radio, television, and film, also video recording; b. seminar, lecture, speech and etcetera; c. map; d. cinematography works; e. voice or sound recording; f. translations; enfornced for 30 years since firs published (2) Copyright on : a. photography work; b. program komputer atau komputer program; c. adaptation and saduran and the arrangement of collective writing; enforced for 25 years since first time published (3) Copyright as mentioned in Article 26 paragraph (1) and Article 27 paragraph (1) possessed or held by a legal institution, enforced for 50 years since first time published, except the Copyright meant in Article 27 paragraph (2) enforced for 25 (twenty five) years. Article 27 Source : Data processed by Saidin by comparing between the Act number 6 of 1982 with the Act number 7 of 1987 In the Act number 7 of 1987, the alteration regarding time period of Copyright protection was conducted in two forms : 1. Regarding the time period itself. 180 2. Regarding the application of the regulation The Act number 6 of 1982 basically provided protection as long as the Author lives and until the 25th year after the Author’s death. That time period lasted for all creations, except photography and cinematography which were for 15 years. The alteration was as long as the Author lives with addition 50 years after the Author’s death. By that, the time period would be longer. In accordance to that alteration, it could be found the reasons of the Government which acted as the background of the alteration of the Copyright Protection. The Government brought forward the reasons and background of the thought which had connection adhered regarding the social function of ownership right. In the explanation, the Government also mentioned the time period “as long as the author lives plus 25 years”, was judged as the form of the social function itself. The thing was enacted for the whole creation, except photography and cinematography, so that the form of the social function principal only limited in the meaning of shortening the time period. As understandable, if Bern Convention was made as the basis, the time period was for “As long as the Author lives plus 50 years”. The thought regarding this was indeed necessary to be reviewed. The realization of social function was not necessary to be translated or realized in the form of short time period. The weakness of the way of thinking which all this time could be reviewed in the case of photography and cinematography. Was because of the protection time period only lasted for 15 years, the Copyright in those two fields could be said had already fulfilled the social function? Was it true that even though the society was impossible to pick any benefit in the time period? From this way of thinking, the Government gave opinion that the time period should be set “as long as the Author lives plus 50 years”. The imaginer limit for 50 years as mentioned, basically also known in the Act number 6 of 1982. Whereas the matter, regarding how to realize the social function more effectively, the Government had introduced a mechanism regarding the obligation to realize the creation or to give license to another party. This mechanism was later known as compulsory licensing. Through this mechanism, the Country saw that it was necessary to judge that a creation or a work was very important to the life of the society. The Country could obligate the Copyright Holder to translate or duplicate the work in Indonesia. The Country could also obligate the Copyright Holder to give the consent or license to another 181 party to translate or to duplicate with the fair fee. With this thinking, the realization of social function was not only formal, but also could be more operational and substantive. Another side of the alteration in this field was in the application or implementation of the regulation. Until today, the time period of the protection is “As long as the Author lives plus 25 years” is generally applied. It means, all of the creation was given protection on its Copyright for the same time. It was not differed from another, for example, between the time period of Copyright protection of a song writer, with the Copyright on the song as possessed by a recording company. By other words, it could not be differed the real (original) Copyright with the derivative Copyright. This is necessary to be concerned from the side of Justice. Based on this thinking, in the Act was then pointed the difference between the time period of the protection by paying attention on the characteristic of the Copyright. Except some creations such as photography, computer program, and creations with the characteristic like collected poetries, which specifically provided protection only for 25 years, then for an original Copyright needed to be provided protection “As long as the Author lives plus 50 years”. This enforced for Copyright such as song or music, book creation, and etcetera. Whereas for the derivative ones, such as music or song recording by the recording company, for book publishing by the publishing company, the Copyright only provided for 50 years. The next alteration was regarding the relationship between countries and Copyright Holder. The Matrix below shall explain that for the national purpose and education, the country can conduct its role to utilize the Copyright. Of course this was conducted without intention to put the other Author in vain and also without the intention that the country would take the commercial benefit. 182 Matrix 16 The Alteration of Act Number 6 of 1982 to the Act Number 7 of 1987 Based on the Relationship between Country and Copyright Holder Altered Substance Materials of Articles Act No. 6/1982 Relationship between Country and Copyright Holder (1) For national purpose, every translation from a foreign language creation into Indonesian or local language shall not be assumed as copyright infringement with provisions: a. creation came from other Country at least three (3) years since published and never translated to Bahasa Indonesia or local language before. b. translator had asked for consent for translating from the Copyright Holder but the consent was not achieved in 1 (one) year since the application proposed. (2) for the translation as mentioned in Article (1) item b, need consent from the Justice Minister. (3) the Justice Minister set the fee to the Copyright Holder in providing consent for the translation hearing the consideration of the Copyright Council as mentioned in Article 39 Alteration Material poured in Articles Act number 7 of 1987 (1) For the purpose of education, science, and activities in research and development, a creation protected copyright and for 3 (three) years after announced not translated in Indonesian or duplicated in the country (Indonesia), the government after listening to the Copyright Council could: A .obliged the Copyright Holder to conduct the translation himself and/or the duplication of the creation in the country of Indonesia in the decided time; b. obliged the Copyright Holder to give consent to another person to translate and/or duplicate the creation in Indonesia for certain time, in the matter of the Copyright himself did not implement himself or stated his unwilling to implement his obligation as mentioned in item a. c. implement himself the translation and/or the duplication of the creation, in the matter 183 Article 15 (1) remembering the provisions in Article 48 Sub b then for national purpose, the creation of non Indonesian citizen and foreign agency can be duplicated for the purpose of use in Indonesian Republic terrirory, with provision: a. creation of non Indonesian citizen, in 2 (two) years announced shall be not enough to be duplicated in Indonesia b.it had been asked for consent to duplicate the creation, but the consent was not achieved in 1 (one) year since the last request proposed (2) Duplication as of the Copyright Holder did not implement the obligation as mentioned in item b. (2) implementation of the provision as mentioned in Paragraph (1) item b and item c with the compensation which amount set by the government. (3) Further implementation regarding the perovision as mentioned in paragraph (1) and paragraph (2) regulated with the Regulation of the Government. Article 15 The government after listen to the consideration of the Copyright Council, can prohibit the announcement of every creation that contradict with the policy of the government in the field of defense and security of the country, morality and general public order”. Article 16 184 mentioned in paragraph (1) item b, shall not be considered as Copyright infringement (3) to duplicate the creation as mentioned in Paragraph 1, consent of Minister of Justice is necessary. (4) the Justice Minister set the fee to the Copyright Holder in giving consent of the Duplication, hearing the consideration of Copyright Council as mentioned in Article 39 Article 16 Source : Data processed by Saidin by comparing between the Act number 6 of 1982 with the Act number 7 of 1987 Two main issues in this field, in accordance with the negation of the provisions regarding the take-over or “expropriation” of a Copyright as regulated in Article 10 paragraph (3) and paragraph (4) the Act number 6 of 1982, and the substitution of the provision in Article 15 and 16 in the “compulsory licensing” mechanism. Differed with another ownership right in intellectual property field, which all born because proposed to and given by the Country. Compared with, for example Patent Company or Brand Company and Trade Mark, and industrial design product which all proposed to and given by the country, the Copyright grow together with the birth of a copyrighted work, a creation. Because of that, it is appropriate to be considered that the take-over to be not conducted. This thing was a bit easier compared with the scoped fields, such as science, art, and literary. In the effort of the development of the vibe of the creation in those fields, the Government suggested that it is not appropriate the take-over to be implemented. At least, even if there were fields necessary for certain goals, or for the application in society, it is enough to be conducted with another better way that is the obligation to conduct or realize the works through compulsory licensing mechanism. This step, will then 185 show more maturity of the society of Indonesia as a nation with sovereignty. In line with that thought, the government was also reviewed the provision of Article 15 and Article 16 of the Act Number 6 of 1982 regarding the “national interest” and its application. As we know, the difficulty this whole time was because we have to explain the definition or limitation of those words. We did not even clearly provide the measurement, criteria, or a definite factor of that “national interest”. In one side, the term was indeed seemed like able to provide a juridical benefit which is very wide in range and unlimited. Even so, if that benefit was really exist, the experience in the application of the Act number 6 of 1982 also showed that the provision in Article 15 and Article 16 can be said as never been realized before, because it has never been utilized before. Besides that, the provisions of both Articles in a whole also need a review in the concept of the thinking. If for instance the “national interest” became the point of departure, then this country is what suppose to be the most authorized party to appoint the existence of the national interest. The Country is the most knowing when the national interest is really needed. It would become a bit peculiar, when the appointment of the existence of the national interest is just given to an individual to judge and to appoint, and then took their own steps in it. Indirectly, that condition would give the impression that the Country, in silence provide a chance and let its citizen to do an activity that put another party in disadvantage. This condition would finally put the country in a very difficult situation, inside or outside. Philosophically, the country is indeed must put more attention to the interest of its society in the utilizing of the Copyright. The Copyright just like the other rights must run the social function and not only for the interest of the Author or the Right Holder. The goal or the idealism of the country was supposed to be able to be read in the preamble of every Act born as the policy or the national legal development policy. The ideological or philosophical opinions can be understood in the preamble of Act number 8 of 1982 and Act number 7 of 1987. For the comparison, it can be seen in this matrix below. 186 Matrix 17 The Regulation Basis of the Publishing of Act number 6 of 1982 and the Act number 7 of 1987 Preamble Act No. 6/1982 a. For the development in the field of law as meant in the General Outline of the Country, the Decree of the Assembly of Representative Number IV/MPR/1978), and also to push and protect the creation, the spread of the cultural result in science, art and literary and also to accelerate the development of the intelligence of the life’s nation in the arena of Indonesian Republic based on Pancasila and The Constitution of 1945, then it is necessary to regulate the Copyright Law; b. that based on the issue in item a then the regulation regarding copyright based on Auteurswet 1912 Staasblad Number 600 of 1912 need to be revoked of its incompetence with the need and the goal of legal future goal. Preamble Act No. 7/1987 a. that providing the legal protection on Copyright basically was meant as an effort to realize a better vibe fort the growth and developing area which have passion in science, art, and literary. b. that in the middle of the implementation of the accelerating national development, especially in science, art, and literary, it is also have been developed the Copyright violation, especially in piracy. c. that the Copyright violation has reached a dangerous rate and it is able to damage the social life order in general and the passion to create in specific. d. that to handle and stop the Copyright violation, it is necessary to alter and perfected some provisions in the Act number 6 of 1982 regarding Copyright. Source : Data processed by Saidin by comparing between the Act number 6 of 1982 with the Act number 7 of 1987 Based on the consideration brought forward by the legislator in the Act number 6 of 1982, it can be understood that inside it, there was basic philosophical consideration containing the ideas and 187 suggestions or goals of the national law establishment. But, that kind of issue could not be seen anymore in the Act number 7 of 1987. The latter Act was said to lost the spirit which gave the leverage to the regulation of that national copyright law. The Copyright Law number 7 of 1987 was enforced for 10 years. In the journey, what had become the suggestion of alteration of the Act was not entirely can be realized. As long as the 10 years enforcement of this Act, the Copyright violation of piracy did not show the good side. Also, the government’s effort to conduct the compulsory licensing to accelerate the use of national interest did not optimally used. Finally the Act must be altered in 1997. E. The Period of Copyright Law Number 12 of 1997 (1997 – 2002) The Act Number 12 of 1997, was the first Act in the field of Copyright Protection in Indonesia after the ratification of GATT 1994/WTO through the Act number 7 of 1994, which contain the TRIPs Agreement and the protocol or the attachments, Indonesia was obliged to adjust its regulation of Copyright with the International Agreement. TRIPs Agreement also obliged the signee countries to subject to the international conventions regarding Copyright such as : Bern Convention and Rome Convention 1961. The Act Number 12 of 1997 though before the born was based on the previous Act, if we see the Act that replaced by it, also was based on the Bern Convention and politically the born of it was influenced by many pressures from Industrial Countries (As countries which have interest with Copyright) especially America. Since early 1980s, America has shown its concern to the important meaning of Copyright protection. This concern was not without reason, because America had other motivation behind the concern. One of the American motivations was, with the level of awareness of the world’s citizen especially the developing countries which had the potential to conduct Copyright violation, then it strengthen the competent of America in the field of technology. Because nevertheless, Copyright is so close with the technology, if the competent of American technology is stronger, then the deficit of the trade of various nation (especially Japan) this issue will strengthen the position of American economy. Moreover, America was hoping that the competition of America in technology would be stronger, this issue would strengthen the existence and trade’s obstacles of American companies outside the nation. This was what Dylan A MacLeodi called 188 as one sided pressure which conducted by America in the Intellectual Property Right Protection Policy as stated: Since the early 1980s, the United States of America has heightened its concern over violations of American intellectual property rights in foreign countries. This concern has been principally motivated by a growing awareness of declining American competitiveness particularly in high technology fields, surging trade deficits with many countries (Japan being the most notable), and the perceived existence of invisible trade walls which keep U.S. firms out of many foreign markets. The United States has been moving both unilaterally and multilaterally to achieve the goal of better protection of American intellectual property rights abroad. The most prominent unilateral measure to be employed has been Section 301 of the Trade Act of 1974, and its offspring ”Super 301” and ”Special 301”. These allow the United States to retaliate against countries that do not adjust their laws and practices into conformity with U.S. requirements.130 The one sided move of America to obtain optimal protection on the American Intellectual Property in many countries especially in developing countries with the implementation of the trade policy. To the countries which was not adjusting the Copyright law with America’s demand, then America could implement economic punishment one sided. At least, that was corrected by Section 301 of the Trade Act 1974. This desire of America then was accepted well in Uruguay Round which resulted the General Agreement of Tariffs and Trade. In that Agreement, the American side emphasized to be provided more protection on intellectual property. This desire then accepted well in the TRIPs Agreement. This was by many community called as “aggressive unilateralism” of America as revealed by Dylan A. MacLeodt. By taking examples in Malaysia, Thailand, and Indonesia, Dylan revealed: The Uruguay Round of negotiations of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) the United States has been pushing for stricter international protection of intellectual property rights. Unilaterally, the United States is evincing a more stringent attitude towards violators of American intellectual property rights. This is 130 Dylan A. MacLeodt, U.S. Trade Pressure and The Developing Intellectual Property Law of Thailand, Malaysia and Indonesia, in Reading Material Hak Kekayaan Intelektual, Universitas Indonesia, Post Graduate Law Faculty, Jakarta, 2007, p. 365. 189 consistent with U.S. trade policy more generally, which one commentator has described as ”aggressive unilaterilsm”. This tougher approach on intellectual property protection manifested itself in 1991 in the designation of Thailand, India and the People’s Republic of China as ”priority foreign countries” under Special 301, which had the effect of warning these countries that without substantial change to their intellectual property law and practies, the United States would employ retaliatory trade measures, Malaysia, Indonesia and Thailand have all been subject to American pressure to alter their respective intellectual property law, although they have responded differently to the American threats of retaliatory trade action Indonesia and Malaysia have moved much more quickly to satisfy U.S. demands and have appreared more willing than Thailand to appease the United States.131 At the beginning, Intellectual Property Rights had not been a part of GATT, but then America’s pressure so the Intellectual Property was put to the GATT’s structure. The disadvantages by America especially the massive piracy of song recording and cinematography in the three countries (Indonesia, Malaysia and Thailand) caused disadvantages in the recording industry in United States. Beside the pressure from America to put the Intellectual property Right in the GATT’s structure, the suggestion was also come from European Community. On July 1988, as written by Agus Sardjono, European Community proposed “Proposal of Guidelines and Objectives” : (1) They should address trade-related substantive standards in respect of issues where the growing importance of intellectual property rights for international trade requires a basic degree of convergence as regards the principles and the basic features of protection. 131 Dylan A. MacLeodt, U.S. Trade Pressure and The Developing Intellectual Property Law of Thatiland, Malaysia and Indonesia, in Journal University of British Colombia Law Review, Vol 26 : (Summer 1992), p. 344. The Uruguay Round had resulted negotiation on some agreements poured in the General of Tariffs and Trade (GATT), America had emphasized that for a better protection on the intellectual property. One sided, America has proved its subjection to the offender of American Intellectual Property Rights. This is in line with the American Trade Politic Generally. One of the Commentators explained it as “aggressive uniteralism”. This gave the conclusion that Copyright protection was given meaning by America itself in 1991 in many meetings in Thailand, India, and Chinese People Republic as “priority countries” under the special regulation 301, and it brought effect also became warning to the countries to conduct big effects on the Copyright Law and the law enforcement in their countries. 190 (2) GATT negotiations on trade related aspects of substantive standards of intellectual property rights should not attempt to elaborate rules which would substitute for existing specific conventions on intellectual property maters, contracting parties, could, however, when this was deemed neccesary, elabrate further principles in order to reduce trade distortions or impediments. The exercise should largely be limited to an identification of an agreement on the principles of protection which should be respected by all parties ; the negotiations should not aim at the harmonization of national laws. 132 Second opinion regarding industrial countries was given by India. India was disagreeing and objecting the suggestion of industry countries to put the intellectual property right in GATT’s structure, because of that, India was not in agreement with that suggestion as taken by Agus Sardjono133 by saying: It would ... not be appropriate to establish within the framework of the GATT any new rules and disciplines pertaining to standards and principles concerning the availability, scope and use of intellectual property rights”. Moreover, Agus Sardjono134 brought forward that the challenges by India regarding the suggestion to put the Copyright Protection in GATT’s structure was based on three important reasons: First, the possessor of the Copyright can conduct what is called by restrictive and anti competitive practices which became obstacle of the international trade. Second, the preincipal and standart regarding the Copyright must first be checked if it is in line with the need of the Developing Countries. Thired, it must be emphasized that the essence of Copyright protection was its characteristic which is monopolistic and restrictive. The Copyright protection would give a very bad effect on the developing countries, remembering 99% of patents in the world is possessed by developed countries. India proposed that Copyright Protection was to be given fully to every country to appoint themselves according to the need and condition in each country. 132 Agus Sardjono, Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia Antara Kebutuhan dan Kenyataan, Establishment Speech of Professor in Private Law in Law Faculty, University of Indonesia, Depok, 2008, p. 5. 133 Ibid. 134 Ibid, p. 8. 191 Even though India objected the suggestion of those developed countries with the reason as mentioned above, finally the issue regarding intellectual property right was also put in the GATT’s structure. That means, the developed countries was succeded in the negotiation and the winning was in their hands. They were even more succeeded when the TRIPs Agreement was made as a protocol to be made next as the structure or reffeence of the signer countries in adjusting or inlining the Copyright regulation in the country. Of course the process of transplantation of TRIPSs Agreement national legislation of each signer country was the consecuention of the developing countries’ failure to object the desire of the developed countries’ desire. By that, i could not be avoided anymore the domination of Western way of thingking which backgrounded by capitalist ideology started to step on developing countries, live with its legal tradition which had different ideology especially in Asian Countries like : Indonesia, Thailand, Malaysia and also India. Indonesia finally ratified the GATT 1994/WTO which included the TRIPs Agreemnt with the consequence that Indonesia must adjust its national Copyright Law (including all regulations related to the intellectual Copyright Protection such as : patent, mark, industrial design, and et cetera). Especially for Copyright Law, Indonesia msut alter back the Act Number 7 of 1987 with the Act number 12 of 1997 by adding some addition Articles and adjusting some Articles inline with TRIPs Agreemnt. Some of the reasons of the alteration will be explained in the next part. Some ideological-philosophical, juridicalnormative considerations and political consideration of the alteration Act number 7 of 1987 with the Act Number 12 of 1997 can be seen in the Preamble: a. That Indonesia is a country with variety of ethnics/tribes and cultures and wealth in art and literature with the developments which needed protection of Copyright in intellectual property which born from those variations. b. That Indonesia has been a member of international convention/agreemnt in the field of Intellectual Property Right commonly, and Copyright especially which i need of the further implementation on the national legal system. c. That the development in trade, industry, and investation has developed enough that i need of more protection for the Author 192 and the Related Right Owner ny paying attention to the interest of the society;135 It is not very clear though, the ideologic – philosophic suggestion pictured in the preamble above, except putting the desires and interests of the foreign to the Indonesian Copyright Law. This explanation was supported by the sentence which stated that : ”Indonesia has been a member of various international convention/agreement” and it needed further implementation in the national legal system”. It is very clear that it can be caught that the legal policy in Indonesia really wanted to transplant the international convention to the National Copyright Law. Of course what was meant is International Convention regarding Copyright such as: Bern Convention, Rome Convention and at last TRIPs Agreement. If the legal policy like these implemented, it is without any doubt that the interest of foreign law would be a primary priority of this Act alteration. Even though the goal of this Act alteration was not just mere like that. In many explanation, there was 3 (three) political consideration (including legal consideration) which also was the goal of the Copyrigt Law alteration number 7 of 1987 to the Copyright Law number 12 of 1997 that are: (1) Providing of legal protection which is becoming more effective to the Intellectual property Right, especially in Copyright need to be accelerated in realizing a better vibe of the growing and developing the spirit to create in science, art and literary, which is needed in the implementation of national development with the goal to realize a fair, welfare, and independent Indonesian society based on Pancasila and Constitution of 1945. (2) Implementing the obligation to adjust the national regulations in the field of Intellectual Property Right including Copyright on TRIPs. (3) Altering and Perfecting some provisions od Act of Copyright number 6 of 1982 regarding Copyright as altered with the Act of Copyright number 7 of 1987 with the regulations. If these three politic considerations (including legal consideration) The Copyright Law number 12 of 1997 compared with the legal consideration used to alter Copyright law number 6 of 1982, it can be seen enough defferences regarding the reason used to conduct the alteration of the law. 135 Preamble Act number 12 of 1997 part Considering item a, b, and c. 193 In the consideration Copyright Law number 7 of 1987 was emphasized more on the Copyright violation which considered had achieved a dangerous rate and can damaged the social structure of the society in general and the passion to create specially. Beside that, it can not be avoided anymore that by the time the Copyright Law Number 1987 enforced, the developed industrial countries powered by United States, pushed the developing countries, including Indonesia, by doing political and economical pressures in the effort to achieve legal protection as good as possible to the Intellectual Property Right’s products marketed in developing country in need. Indonesia is one of the developing countries which in fear of not accepting anymore beneficial treatment by United States which acted as the soldier in the developed industrial countries.136 The legal consideration used in Copyright Law number 12 of 197 to alter the Copyright law number 7 of 1987 as contained in the preamble, caused the Indonesia’s membership in the international convention/agreement such as TRIPs Agreement137 which was a part of the agreement of the making of World Trade Organization brought effect on the occurance of the obligation to adjust national legislation in the field of Intellectual property Right including Copyright. The reasons of the alteration can be found in the explanation on the Act number 12 of 1997 regarding the Act number 7 of 1987 of Copyright: 136 Read Sudargo Gautama, Pembaharuan UUHC 1997, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, p. 129. 137 With the membership of Indonesia as developing country in the TRIPs Agreement would cause certain benefits as one of the example is brought forward in the writing by UNCTAD Secretariat with the title The Trips Agreement and Developing Countries, New York and Geneva, 1996 ; p. 38 : Literary and artistic creativity is universally distributed, and situational disadvantages seldom preclude authors in developing countries from entering domestic or foreign markets. Many developing countries participate fully in these markets. Such rights thus become vehicles for the development of authonomous cultural industries everywhere and for the preservation and enhancement of the developing country’s own cultural heritage. Even mandatory recognition of neighbouring rights affords opportunities to countries whose music, dance and folklore are important components of the national heritage, as attested by the fact that over half of the parties to the Rome Convention are developing countries. Hence, authors of literary, artistic and scientific works in all member countries may benefit from a strengthened protection of their rights on an international scale. Cinematographic authors, in particular, have explicitly recognized rental rights under the TRIPS Agreement, although subject to a broad exception (Article 11). This recognition may benefit many developing countries, particularly those that have been able to develop strong film industries. 194 First, there was a will from the Government to react to the Decree of the Representative Assembly Number II/MPR/1993 regarding the Outline of the State Policy which asserted that the development of the world, containing chances that accelerate the national growth, need to be utilized well. In accordance with the Outline of the State Policy, every development, alteration, and another global issues which predicted can influence the Ntional Stability and the achievement of national goal also need to be followed carefully, so the steps to anticipate can be taken. One of the stunning development that got attention in this last ten decades and has possibitiy to still be given attention for the future is the widespread of the globalization in social, economy, culture, or in the other fields. In the field of trade, especially because of the development in information technology and trasportation, has made the activity in this sector increased and even placed the world as a single market together. By paying attention to this reality and tendency, it was becoming more understandable that the demand to regulate for legal protection was necessary. Much less some country were counting on economic activity and its trade on products that resulted by the intelligence of human such as works in the field of science, art, and literary. Second, there was will from Government to assist the acceleration of the world’s economic growth and to respond well to the General Agreemnt on Tariff and Trade (GATT) which was a multilateral trade Agreement. This choice was actually an economic policy launched by capitalists countries to create the free trade bt providing the same treatment to international businessmen in many parts of the world. The aim was to after the economic growth in order to objectify the welfare of the human. Third, there was a belief from the Government that by creating the legislation in line with TRIPs Agreement can support national economic activity. TRIPs Agreement contained norms and standards of protection for the intellectual works of human and placed the international Agreement in the field of Intellectual property as the basis. Beside that, the Agreement was also regulate the legal implementation regulation in the field of Intellectual Property Right strictly. As a signing country of the Uruguay Round Agreement, Indonesia had ratified the Agreement package with the Act number 7 of 1994 regarding Agreement Establishing The World Trade Organization. In line with that policy, to support the national growth activity, especially by paying attention to various development and alteration, Indonesia that already had Copyright Law since 1982 which 195 then perfected with the Act number 7 of 1987, need to make another improvement with the Law. Beside to improve some provision which was felt not giving enough protection to the Author, it was also felt necessary to ma make adjustment with the TRIPs Agreement. The goal was to delete obstacles especially to provide supporting facilities to increase the economic growth and the trade, both national and international. Referring to the consideration above, the Act number 7 of 1987 needed to be altered to answer the challenge and also to accomodate the will and hope as referred to. With Indonesia that has become the member GATT 1994/WTO officialy, which inside the Agreement contained the TRIPs Agreement, then the latter Agreement was made as the framework in regulating Intellectual Property Right Law in Indonesia, including Copyright Law. This following matrix shows us some provision in TRIPs Agreement that transplanted into the Act number 12 of 1997. Matrix 18 Transplantation of TRIPs Agreement into the Act Number 12 of 1997 Regarding Rental Rights Substance TRIPs Agreement Act No. 12 Tahun 1997 Rental on Copyright must obtain the consent from the Author or Right Holder. (Article 1 paragraph (2) and(3)) Rental rights In respect of a least computer program and cinematographic works, a Member shall provide authors and their successors in title the right to authorize or to prohibit the commercial rental to the public of originals or copies of their copyright works. A member shall be excepted from this obligation in respect of cinematographic works unless such rental has led to widespread copyring of such works which is materially impairing the exclusive right of reproduction conferred in that Member on authors and their successors in title. In respect of computer program, this obligation does not apply to rentals where the program itself is not the essential object of the rental. (Article 11) Source : Data processed by Saidin by comparing the Act number 12 of 1997 with TRIPs Agreement. 196 The matrix above showed that, the power of the will of the developed countries to protect the works in computer program and the cinematography was so strong that Indonesia must transplanted Article 11 of the TRIPs Agreement to the Article 2 paragraph (2) and paragraph (3) the Act number 12 of 1997. Whereas, if systematically analyzed, Copyright is an intangible object and because of that, subject to legal object principle in terms of the transfer of the right and also in renting which subject to law of engagement. By transplanting Article 11 TRIPs Agreement to Article 2 paragraph (2) and paragraph (3) the Act number 12 of 1997, then this legal norm would be out from object legal system and deviated from engagement law system. The principal adhered by object law was: Anybody who has already obtained the transfer of object right perfectly, then the possessed object would be his possession and the consequence would be that the owner has an absolute right on the object. This legal principle was out from the object legal system when someone buy VCD and DVD of cinematography must ask the consent of its Author or Right Holder to be rented to the third party. This article was so perfect to adopt the capitalist values in managing the economic sources. By other words, capitalist ideology from the Western Law has been transplanted perfectly by the legislator of National Copyright Law by transplanting Article 11 TRIPs Agreement into Article 2 paragraph (2) and paragraph (3) Act number 12 of 1997. Matrix 19 Transplantation of TRIPSs Agreement into the Act number 12 of 1997 Regarding Neighbouring rights Subst ancei Neig hbouri ng rights Rome Convention 1961 PERFORMANCES PROTECTED. POINTS OF ATTACHMENT FOR PERFORMERS Each Contracting State shall grant national treatment to performers if any of the following TRIPs Agreement Protection of Performers, Producers of Phonograms (Sound Recordings) and Broadcasting Organizations 1. In respect of a fixation of their performance on a phonogram, performers shall have the possibility of preventing the following acts when undertaken Act number 12 of 1997 (1) The offender has special right to give consent or prohibit people without consent to make, duplicate, 197 conditions is met: (a) the performance takes place in another Contracting State; (b) the performance is incorporated in a phonogram which is protected under Article 5 of this Convention; (c) the performance, not being fixed on a phonogram, is carried by a broadcast which is protected by Article 6 of this Convention. (Article 4) PROTECTED PHONOGRAMS: 1. POINTS OF ATTACHMENT FOR PRODUCERS OF PHONOGRAMS; 2. SIMULTANEOUS PUBLICATION; 1. Each Contracting State shall grant national treatment to producers of phonograms if any of the following conditions is met: (a) the producer of the phonogram is a national of another Contracting State (criterion of nationality); (b) the first fixation of the sound was made in another Contracting State (criterion of fixation); (c) the phonogram was without their authorization: and the fixation of their unfixed broadcast performance and the the reproduction of such recording fixation. Performers shall and or also have the possibility of picture preventing the following from the performanc acts when undertaken without their authorization: e. Pelaku the broadcasting by memiliki. wireless (2) Recording producer means and the communication to the has a public of their live special performance. right to give 2. Producers of phonograms shall enjoy the right to consent or authorize or prohibit the prohibit people direct or indirect without reproduction of their phonograms. consent to 3. Broadcasting duplicate the organizations shall have the recording right to prohibit the following acts when of voice or undertaken sound. without their authorization: (3) Broadcastin the fixation, the reproduction of fixations, g institution has special and the rebroadcasting by right to wireless give means of broadcasts, as well as the communication consent or prohibit to the public of television people broadcasts of the same. without Where Members do not consent to grant such rights to make, broadcasting organizations, duplicate, they shall provide owners and reof broadcast copyright in the subject the record matter of broadcasts with through the possibility of preventing transmissio the above acts, subject n with or to the provisions of the 198 first published in another Contracting State (criterion of publication). 2. If a phonogram was first published in a non–contracting State but if it was also published, within thirty days of its first publication, in a Contracting State (simultaneous publication), it shall be considered as first published in the Contracting State. 3. By means of a notification deposited with the Secretary– General of the United Nations, any Contracting State may declare that it will not apply the criterion of publication or, alternatively, the criterion of fixation. Such notification may be deposited at the time of ratification, acceptance or accession, or at any time thereafter; in the last case, it shall become effective six months after it has been deposited. 1961 (Article 5) PROTECTED BROADCASTS: 1. POINTS OF ATTACHMENT FOR Berne Convention (1971). without 4. The provisions of Article cable, or 11 in respect of computer through programs shall apply another mutatis mutandis electromag to producers of phonograms netic and any other right holders system in phonograms as ((Articlel 43C) determined in a Member's law. If on 15 April 1994 a Member has in force a system of equitable remuneration of right holders in respect of the rental of phonograms, it may maintain such system provided that the commercial rental of phonograms is not giving rise to the material impairment of the exclusive rights of reproduction of right holders. 5. The term of the protection available under this Agreement to performers and producers of phonograms shall last at least until the end of a period of 50 years computed from the end of the calendar year in which the fixation was made or the performance took place. The term of protection granted pursuant to paragraph 3 shall last for at least 20 years from the end of the calendar year in which the broadcast took place. 6. Any Member may, in 199 BROADCASTING ORGANIZATIONS; 2. POWER TO RESERVE 1. Each Contracting State shall grant national treatment to broadcasting organisations if either of the following conditions is met: (a) the headquarters of the broadcasting organisation is situated in another Contracting State; (b) the broadcast was transmitted from a transmitter situated in another Contracting State. 2. By means of a notification deposited with the Secretary– General of the United Nations, any Contracting State may declare that it will protect broadcasts only if the headquarters of the broadcasting organisation is situated in another Contracting State and the broadcast was transmitted from a transmitter situated in the same Contracting State. Such notification may be deposited at the time of ratification, acceptance or accession, or at any time thereafter; in the last case, it shall relation to the rights conferred under paragraphs 1, 2 and 3, provide for conditions, limitations, exceptions and reservations to the extent permitted by the Rome Convention. However, the provisions of Article 18 of the Berne Convention (1971) shall also apply, mutatis mutandis, to the rights of performers and producers of phonograms in phonograms. (Article 14) 200 become effective six months after it has been deposited. (Article 6) Source : Data processed by Saidin by comparing the Act number 12 of 1997 with TRIPs Agreement. Also with the entry of the Article regarding neighbouring right into the Copyright Law number 12 of 1997 was transplantation result from Article 14 from TRIPs Agreement which adopted before from Article 4, 5 and 6 of Rome Convention of 1961. Of course the transplantation of this TRIPs Agreement was a realization of the winning of developed countries to the developing countries to put in the suggestion of neighbouring right protection to the National Copyright Law in the countries including Indonesia. It is necessary to understand that TRIPs Agreement is a cooperation break-trough in international trade which point is that to guard the interest of developed industrial countries as countries which gave birth to Intellectual Property Right. It is unimaginable if the broadcasting right or the performance of the actresses or actors in developed countries being broadcasted through electronic media, but then the broadcasting right must be paid or at least the broadcasting must first obtained consent first from the Right Holder which was in the the category of right which had connection with Copyright (neighbouring rights). For developed industrial countries, these kinds of thing were something natural. But for developing countries, the royalty for paying the neighbouring rights would be production burden in broadcasting in electronic media. All this production burdens would be held by broadcasting industry which in turn would also held by the commercial owner and the commercial finally would become burden for the society as the consumer of the products in the commercial. This is what would go on for the sake of developed countries in order to have protection of the intellectual property rights in the whole world (at least in the signer countries of TRIPs Agreement) through each national’s legislation. Also with the entry of license regarding license as regulated in Article 21 TRIPs Agreement in Article 38A, 38B and 38C Act number 12 of 1997 was as a prove of Indonesia’s weak position in fighting for the national interest when facing with developed countries in Uruguay Round which resulted GATT/WTO Agreement. The following matrix 201 showed the legal norms of TRIPs Agreement which transplanted into the Act number 12 of 1997. Matrix 20 Transplantation of TRIPS Agreement into the Act number 12 of 1997 Regarding Copyright License Substance Copyright Substance TRIPs Act No. 12 Tahun 1997 Agreement Licensing and (1) Copyright Holder is entitled to Assignment provide license to another party Members may based on license agreement determine letter to implement action as conditions on the referred in Article 2. licensing and (2) Unless promised otherwise, then assignment of the scope of license as said in trademarks, it paragraph 1 was on all actions being as said in Article 2 is on for as understood that long as the time period of license given and enforced for the compulsory every territory of Republic of licensing of Indonesia. trademarks shall not be permitted (Article 38 A) and that the Unless promised otherwise, then the owner of Copyright Holder can conduct a registered himself or provide license to the trademark shall other third party to implement the have the right to action as said in Article 2. assign the (Article 38B) trademark with (1) The license Agreement is or without the prohibited to contain provision direct or indirectly can cause transfer of the effect that put Indonesian business to economic state to be in vain. which the (2) for having legal effect on the trademark third party, the license belongs. Agreement must be listed in the (Article 21) Copyright office. (3) the license Agreement listing request that contain provisions as said in paragraph (1) must be 202 rejected by Copyright office. (4) further provision regarding the license, including the listing method regulated further with Government Regulation. (Article 38 C) Source : Data processed by Saidin by comparing the Act number 12 of 1997 with TRIPs Agreement. The interest of developed countries dominantly placed in the Act number 12 of 1997 which transplanted from Article 21 TRIPs Agreement. License was reallt attached with the protection of Intellectual Copyright which connected with investment. Investment always present in the shape of technology. If technology that invested would be implemented in one country by one nation, then the requirements asked by the country that would do the investment was the security on the Intellectual property Right protection in the country where the investment being placed. Usually, the ones who need those investments are the developing countries. When the developing countries could not provide protection to the Intellectual property Rights then the investors from developed countries were reluctant to invest in those developing countries. License is and instrument from investment that need to be protected. America and other developed industrial countries had even made important requirement of Intellectual Property Right for the choice to do investment, as William C. Revelos 138 stated cited by Agus Sardjono. The other parts which got addition was more meant to strengthen or emphasize the need of original element of one work to obtain Copyright Protection. A work must have typical shape and show the originality as someone’s creation based on the personal ability and creativity. In a typical shape, means that the work must have been realized so it can be seen, listened, or read. Including in definition of readable thing is the read of Braille alphabet. Because a work must be realized in typical shape, then the Copyright protection could not be given just in idea. According to this provision, an idea basically did not 138 William C. Revelos, Patent Enforcement Difficulties in Japan : Are There Any Satisfactory Solution for the United States, George Wahington Journal of International Law and Economy, (Vol. 29, 1999), p. 529. 203 obtain any Copyright protection. Because idea has not possessed a shape which is possible to be seen, listened, or read. Also, regarding the phrase, “offender”. In this legislation, it is need to be emphasized that the actual offender phrase was actually base on the TRIPs Agreement which regulate the neighbouring rights. Because of that, addition to the definition of offender must be added. In the definition of performers, the mentioning of actor, singer, musician and dancer showed the profession which basically stated some of them whose activity were to perform, act, show, sing, convey, declaim or to play a creation. Whereas the definition of voice recording producer is they who conduct the activity of direct recording on object who publish a voice or a sound, including they who record voice or voice by arranging differently, and not only by duplicating the existed recording. The stated creation meant was in definition of recording institution of audio, visual, or audiovisual. The broadcasting was for audio, and audiovisual. The requirements in the shape of legal entity only enforced for Private Broadcasting Institution. Beside the addition of material such explained above, in the Act number 12 of 1997 was also altered from the enforced Act before, that was Act number 7 of 1987. The alteration can be seen in matrix below. Matrix 21 Alteration of Act number 7 of 1987 to the Act number 12 of 1997 Based on Protection Aspect on unknown creator or a creation Altered Substance Protection on unknown creator of a creation Material of Articles Act number 7 of 1987 When a creator of a creation is not known at all, then Country hold the Copyright on that creation unless proven Alteration Material poured in Articles Act number 12 of 1997 Materi (1) If a creation is unknown of the creator and the creation has not been published yet, then Country hold Explanation Country takes over the Copyright which Creator is unknown, but the take over was conducted for the purpose of 204 otherwise. Article 10 A Source : the Copyright on that Creation for the purpose of its creator. (2) If a creation has been published but the creator is unknown or on the creation only stated the false name of the creator, then the Publisher hold the Copyright on the creation for the purpose of the Creator. Article 10A the Creator. Data processed by Saidin by comparing between Act number 7 of 1987 with Act number 12 of 1997. The first alteration was regarding protection of the unknown, in this case, the Country would take over the ownership for the sake of the Creator which before, the word of “for the sake of the creator” was not mentioned in Act number 7 of 1987. This alteration was meant to emphasize the status of Copyright in an unknown work which is not or has not been published yet, as if the creation is realized. For example, in written or musical work, the creation has not been published in the form of book or recording yet. In that case, then Copyright on that work was held by the Country to protect the Copyright for the purpose for the Creator, whereas the creation was a published written work, then the Copyright on that certain Creation was held by the Publisher. 205 The Publisher was also considered as the holder of the Copyright on the published creation using the false name of its Creator. By that, a published creation but unknown of the creator or on the creation only stated the false name of the creator, the publisher stated in the creation which can prove as the first one to publish the creation, shall act on behalf of the Creator. This is not applied when the Creator then stated his identity and he can prove that the Creation was his Creation. Matrix 22 Alteration of Act number 7 of 1987 to the Act number 12 of 1997 Based on the exception of Copyright Violation Altered Substance Exception of Copyright Violation Material on Articles of Act number 7 of 1987 (1) If a creation was made in official relation with another party in the working environment, then the party which for and in the official of the creation done was the Copyright Holder, unless there was another agreement between both parties, without decreasing the right of the Creator, as the Creator when the us of the Creator was beyond the official relation. (2) If the creation was made in working relation with another party in the Material of Alteration which poured in Article of Act number 12 of 1997 (1) If a creation was made in the official relation with another party in the working environment, then the party which for and in the official the creation was done, was the Copyright Holder, unless there was another agreement between both parties without decreasing the right of the Creator as the creator if the use of the creation was made beyond the official relation. (2) Provision as stated in Article (1) enforced for Creation made by another party based on the order made in official relation. (3) if a Creation was made in working relation or based 206 working environment, then the party who made the work was the Copyright Holder, except promised otherwise between another party. Source : on order, then the one who made the creation was considered as the Creator and Copyright Holder, unless promised otherwise by both parties. (Article 8) Data processed by Saidin by comparing between The Act number 7 of 1987 and Act number 12 of 1997. The matrix above added the norm regarding the exception of Copyright violation. The adding of the provision was to emphasize the principal that Copyright on a creation made by someone based on order, for example from the Government, unless promised otherwise, was held by the Government as the Creator if the Creation was used for anything beyond the official relation. If there was creation used for the matter beyond official relation meant to make clear the existence of Copyright in the matter of the Creation was born or made outside official relation or based on order. Which means, the creation was made in the working relation in private environment or made based on order from private institution with another party or between individual with individual. Matrix 23 Alteration of Act number 7 of 1987 to the Act number 12 of 1997 Regarding the Time Period of the Work’s Protection Altered Substance Works’ protection time period Material of Articles in Act number 7 of 1987 (1) Time period of the enactment of copyright on the creation announced part by part, counted started since the last part of the announcement Alteration material poured in Articles in Act number 12 of 1997 (1) Copyright on creation held or implemented by nation based on: a. Provision Article 10 paragraph (2) item b, enforced in unlimited time. b. Provision Article 10A paragraph (1), enforced for 50 (fifty) years since the work first known by public. 207 date (2) in appointing the enactment time period of the work’s copyright which is more than 2 (two) versions or more, also the summary and news announced in printed media in different time, then every version or summary and the news each considered as its own creation. (2) Copyright on creation which implemented by publisher based on provision of Article 10A paragraph (2), enforced for 50 (fifty) years since the work first published. Article 27A Article 28 Source : Data Processed by Saidin by comparing the Act number 7 of 1987 with the Act number 12 of 1997. The addition of this new provision was meant to clarify the provision regarding the time period of protection for creations which Copyright held by the country. The principal was, the creation which copyright held by nation, provided with unlimited time protection. Whereas for the creation which Copyright implemented by nation provided with protection for 50 (fifty) years since the creation known by society. This provision enforced on creation which author was unknown. If then the identity of the author was known, or the author itself then brought forward the identity in 50 (fifty) years after the creation known by society, then what would be enacted was the provision of Copyright protection in 50 (fifty) years after the Author passed away. Also for creation which Copyright implemented by publisher, the protection lasted for 50 (fifty) years since the creation first published. 208 Matrix 24 Alteration of Act number 7 of 1987 to Act number 12 of 1997 Regarding the Right and Authority to Accuse Altered Substance Rights and Authority to Accuse Source: Material of Article of Act No. 7/1987 Copyright provide right to foreclose the goods announced which contradicted the copyright also unauthorized duplication, with ways and paying attention on provision stated for the foreclosure on moving object both for the handover or for the suing for the handover so the object can be in his possession or to accuse for the object to be destroyed so it cannot be used anymore. The Copyright also provide the same right to foreclose and accuse on amounts of entry money for attending seminars, performance, or exhibition which violate the Copyright. Article 42 paragraph 1 Alteration Material poured in Articles Act number 12 of 1997 Copyright Holder is entitled to propose compensation accusation to the court on Copyright Violation and ask for closure on the object announced or the result of the duplications. Article paragraph 1 42 Data processed by Saidin by comparing the Act number 7 of 1987 and the Act number 12 of 1997. The alteration was meant to simplify the provision and to emphasize the right of Copyright Holder to propose compensation accusation. In that event, foreclosure as mentioned in the alteration must be done by looking at the provision regarding foreclosure of moving objects as regulated in Private Practical law. As a matter of fact, the alteration regarding law enforcement of the Copyright was included in the accusation was one thing implicated by Article 42 the TRIPs Agreement. TRIPs Agreement was also emphasizing in Article 43 regarding the verification on Copyright law violation and it must be poured by the Intellectual property Right Law of Indonesia. Because of that, TRIPs Agreement emphasized the 209 aspects regarding law enforcement and the Dispute Resolution with the tools that must be poured by Intellectual Property Right provision regulated in Indonesian National legislation including Copyright. Tight law enforcement aspect was one factor that needed to be looked at by countries that ratified the GATT 1994/WTO. Signer countries of this convention also need to provide legal enforcement mechanism in the private practical law. That what was implicated from article 44 TRIPs Agreement. By that, it can be assured that the compensation accusation and others that has been discussed by Article 42 paragraph (1) Act number 12 of 1997 was also the thing implicated by Article 45 TRIPs Agreement. Also, about the destruction on the objects which was the result of Copyright violation, also implicated by Article 46 TRIPs Agreement. Also TRIPs Agreement implicated in Article 50 for the Court to publish temporary decree to prevent bigger disadvantages for the Copyright Holder. All provisions in TRIPs Agreement started from Article 42 to Article 46 and Article 50 were the provisions regarding law enforcement of Copyright that needed to be transplanted by National Copyright Law from TRIPs Agreement. Looking at Articles in Act number 12 of 1997, it can be ascertained that only some of the Articles in TRIPs Agreement regarding law enforcement that has been transplanted. But even so, it can be ascertained that Indonesia showed its compliance dynamic to the provision in TRIPs Agreement and also proving that the transplant of TRIPs Agreement into the national Copyright Law has been implemented without seeing the norms substance in the regime of TRIPs Agreement from the school of thought of individualism, materialism, and capitalism. If in the later day the law enforcement of the Copyright do not go in line with the legislation, that is not merely because Indonesian citizen don’t comply with the law, but because the legislation did not based on the spirit and the values adhered by the people of Indonesia. 139 139 Based on the research done by Agus Sardjono, legal culture of Balinese people differed from the legal norm meant by Intellectual Property Right Law. Legal Culture of Balinese people based on religious and communal view whereas the regulation of Intellectual property Right Law in Indonesia adopted the materialistic and bring forward individual rights. Western communities see that the source in earth was something that can be exploited whereas Indonesian traditional society see that human is just the custodian of the source in earth. See further Agus Sardjono, Op.Cit, p. 48-49. 210 Matrix 25 Alteration of Act number 7 of 1987 to the Act number 12 of 1997 Regarding Civil Servants Investigator Altered Substance Civil Servants Investigator Source : Material Articles Act number 7 of 1987 Certain Civil Servants Investigator in Department of Justice provided special Authority as Investigator as stated in Act number 8 of 1981 regarding Criminal Practical Law to conduct investigation of the criminal act in Copyright. Article 47 paragraph (1) Substance Material poured in Articles Act number 12 of 1997 Beside the State Police officer Investigator of Indonesia, also the Civil Servant Investigator in departments which duty and responsibility was to develop the Copyright, provided with special Authority as Investigator as stated in Act number 8 of 1981 regarding Criminal Practical law to conduct investigation of Criminal Act in Copyright. Article 47 paragraph (1) Data processed by Saidin by comparing between Act number 7 of 1987 with Act number 12 of 1997. Also regarding the provision regarding the mechanism of criminal law enforcement was also mechanism implicated by TRIPs Agreement even though the norms associated with that was defined differently in national Copyright Law in each Country, but the standard norms that must be fulfilled were regarding provisions of law enforcement, dispute resolution mechanism and another tools related to the compensation and the actions in cross retaliation. The alteration regarding the authority if Civil Servant Investigators, and the mechanism of duty implementation and the relation with State Police officer Investigator of Republic of Indonesia, and public prosecutor, was a provision that implemented by TRIPs Agreement. Regarding this investigation, it’s important for the investigators in implementing the duty. So, a confirmation than even 211 though the Civil Servant Investigator in departments which duty and responsibility was the development in Copyright, provided with special authority as Investigator, but it will not abolish the function of State Police officer investigator of Indonesia as the main Investigator. In implementing its duty, the Civil Servant Investigator was under coordination and supervision of State Police officer Investigator of Republic of Indonesia. In this phase the State Police officer Investigator provide a clear clue technically regarding the shape or form and the contain of news and also to research the material truth of the news of investigation. After the investigation finished, the result of the investigation is to be submitted to the Civil Servants Investigator of Indonesia which after that is obliged to be delivered to the Public Prosecutor. This is in line with the principle asserted in Article 6, 7 and 107 of Act number 8 of 1981 regarding Criminal Practical Law. In this school of thought, the word “through” does not have to be defined that the State Police Officer Investigator at the time or as long as the Civil Servant Investigator conduct the investigation. With that, the principle of speed and effectiveness as desired by the book of criminal practical law really can be realized. But in the practice of law enforcement, the Act number 12 of 1997 also not functioned as hoped. The developed countries which first emphasize the need to aggravate the criminal threats and the need to prepare the law enforcement mechanism turned out to feel the piracy activity and Copyright violation was not merely can be stopped with the perfection of the legal norms. Many reports and information proved that after the enactment of Act number 12 of 1997, the piracy was getting worse. Indeed in 2000, Indonesia was ever free from the Priority Watch List of United States on Intellectual Property Right Piracy conducted by the people of Indonesia. But in April 2001 Indonesia was back into the blacklist of Copyright piracy. This condition then became the reason to developed countries to push Indonesia to re-perfect the Copyright Law which only lasted for 5 years, because at last, the Act number 12 of 1997 must be revoked and replaced by Act number 19 of 2002. The 5 years period of the enforcement of the Act number 12 of 1998 was the period where Indonesia has ratified TRIPs Agreement and adjusted the legislation with TRIPs Agreement and also prepared for related instruments in law enforcement, but the things cannot answer that the activity of Copyright violation or piracy can be stopped or at least quantitatively be reduced. 212 F. Period of Copyright Law Number 19 of 2002 (2002 – 2014) The experience of Indonesia from time to time in order to protect and grow the Author’s creativity formed in National Copyright Law was proving to have many failures. Also when Indonesia was obliged by developed countries to adjust the national Copyright Law with TRIPs Agreement, as the “winning result” of developed country versus developing countries, it turned out that Indonesia which has subjected to the Agreement to not having any result as hoped for the protection of Copyright. Specifically on the cinematography works realized in VCD and DVD. The question that always questioned in every academician’s mind which pay attention on the legal aspect of Copyright protection was why Indonesia kept following the message of developed countries and kept conducting adjustment of its Copyright Law with TRIPs Agreement if this option is not giving any benefit for most society of Indonesia. The obtained answer was very simple. This choice conducted by Indonesia was a pragmatist choice that was for Indonesia to not be excommunicated from global trade which expected to cause benefit for Indonesia in a whole. This was what meant by Joseph Margolis as pragmatism without foundations.140 Whereas the building of the Nation of Indonesia has been put in one foundation, that is Pancasila. 141 But the regulation of the national Copyright Law because of the pragmatist choice, caused the foundation of Pancasila abandoned. This is not without the development of the world that runs today. Indonesia or the world 50 years ago is different with Indonesia that can be seen or felt today. One of the actual development and provided with attention in this decade and the likelihood to still be conducted in the future was the widespread of globalization in social, economy, culture, or anther fields. In the field of trade, it is especially because the development of information and transportation technology has massively grown and made the world as a single market for all.142 By paying attention on the truth and the likelihood like that, then it was becoming more understandable that the claim of need for the regulation for a better 140 Joseph Margolis, Pragmatism Without Foundations, Continium International Publishing Group, New York 2007, p. 138 141 Kaelan, Negara Kebangsaan Pancasila Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya, Paradigma, Yogyakarta, 2013. 142 See further Nanang Indra Kurniawan, Globalisasi dan Negara Kesejahteraan: Perspektif Institusionalisme, UGM, Yogyakarta, 2009. Also see Rahayu Kusasi, Meracik Globalisasi Melalui Secangkir Kopi, Kepik Ungu, Jakarta, 2010. 213 legal protection. Also some countries counted more on economic activity and the trade on products resulted on intellectual ability of human as works in the field science, art, and literary. The General Agreement on Tariff and Trade/GATT which is a Multilateral Agreement on Trade which basically has the goal to create a free trade, similar behavior, and assist to create economic growth and development to realize human welfare. 143 In the matter of the multilateral agreement, on April 1994 in Makaresh, Morocco, a package of result of the most complete GATT ever produced had been agreed. The Discussion that has been started since 1986 in Punta del Este, Uruguay which was known as Uruguay Round contained Agreement regarding Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPs. TRIPs Agreement contained norms and protection standards for human intellectual work and placed international agreement in Intellectual Property Right as the basis.144 Besides that, the Agreement also regulates the implementation on law enforcement in Intellectual Property Right tightly. The messages contained in this Agreement actually had been transplanted by Indonesia into the National Copyright Law after Indonesia ratified the Convention regarding the formulation of World Trade Organization which also contain the Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right/ TRIPs as verified with the Act number 7 of 1994 regarding Agreement Establishing the World Trade Organization. The Ratification on the regulation supported Indonesia’s membership in Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, as verified with Presidential Decree of Indonesia number 18 of 1997 in May 7th 1997 and WIPO Copyright Treaty which also had been verified with Presidential Decree of Indonesia number 19 of 1997 in May 7th 1997, followed by implementing the obligation to adjust the national legislation in the field of Copyright to that international Agreement, so that to support the activity of national growth, especially by focusing on many developments and alterations, Indonesia which since 1982 has had legislation regarding national Copyright which then perfected with Act number 7 of 1987 and perfected again with Act number 12 of 1997, needed to alter the Act to adjust with the standards as pointed in the International Convention. But after the national Copyright Law of 143 See further Mohammad Hatta, Masalah Bantuan Perkembangan Ekonomi Bagi Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1967. 144 See further Achmad Zen Umar Purba, Intellectual Property Right Pasca TRIPs, Alumni, Bandung, 2006. 214 Indonesia regulated based on the messages demanded by TRIPs Agreement which poured in Act number 12 of 1997, it turned out, there was still things which considered as not appropriate with the will of developed countries which powered the birth of TRIPs Agreement. Whereas if compared with the previous Acts, the Act number 12 of 1997 was far more appropriate with TRIPs Agreement. The Act number 12 of 1997 showed the difference with the previous Acts such as: 1. The scope of creation which provided with perfected protection, that was the work of voice recording, was deleted from the protected works and only provided with protection in the rights related with Copyright. This was implemented in order to prevent confusion as if the voice recording was protected by Copyright and also by Related Rights with Copyright; 2. Also the database intellectual creation was put in as one of the creations protected as demanded by WIPO Copyrights Treaty (WCT), where Indonesia had signed the Agreement; 3. Escalation of time period of the Copyright protection is as long as the Author lives with addition of 70 years. This was meant to provide a more passionate vibe for the Authors to make creation and the Copyright protection on the Author’s heir, which is longer, beside that to adjust with the likelihood of international prevalent that protect it more than 50 (fifty) years. 4. In the matter of Dispute Resolution, this Act has assigned the settlement by Commercial Court and also another Alternative Dispute Resolutions such as Arbitration, Mediation, etc; 5. Another thing added in this Act was the introduction of temporary system decree of the Court as demanded in Article 50 in TRIPs, to enable further prevention of the disadvantages of the Right Holder, and also keep the interest of party who subject to the temporary decree of the Court in balance. 6. Another addition was the establishment of criminal threats on violation of related rights with the Copyright, which in the previous Copyright Law, the criminal threats only enacted mutatis-mutandis. 7. The addition of Criminal provision of maximum fine in this Act was meant to tackle the Copyright violation so the effectiveness of the action can be realized. 215 8. The time limit of the process in Copyright handled by the Commercial Court, this is to provide legal certainty and prevent the protracted handling of and issue of Copyright which have a very wide effect in economy and trade. 9. Addition of provision regarding information of electronic management and technology control tool to be adjusted with provision in WIPO Copyright Treaty (WCT) The real job of the legislation institution is actually to create the feel of justice, legal certainty and biggest welfare to the society, not to create or shape the law or to give birth or produce as many Act as it can. It is not the quantity of the legislation that become the target of the job of legislation institution, but the quality of the born legislations. That is also the goal that should be after in formulating Copyright Law. The goal is of course not to fight its own nation. When the Copyright Law number 19 of 2002 implemented repressively by maximizing the function and role of the police as investigator, even though the character of the delict in the legislation was placed as regular delict, not delict on complain, but with the proactive of the police in conducting inspection on the pirated works, a lot of pirated VCD/DVD sellers caught and the pirated works then confiscated. This activity is potential to “grind” the street vendors who run this activity daily. Involved stake holders in the business based on the works of the piracy are also plenty. Starting with the producers of the pirated works, distributors, sellers, and the consumers. Not all of the consumers aware that the trade of the pirated VCD/DVD is a criminal action. What will be the fate of the children of this nation if the Act number 19 of 2002 is really implemented, because 90% of VCDs and DVDs circulated in Indonesian market are the result of piracy and it also means that 90% of the consumers of VCDs and DVDs in Indonesia were consumers who have potential to be convicted. 145 This is the Act that was born to declare war to its own nation. If this keeps going on, there must be something wrong in the management of this nation. This law or legislation has been amended 4 times and followed by the aggravated of the threat of criminal charges. But that does not change the situation that the infringement or Copyright piracy will be decreased or stopped, what will happen is actually the contradiction, the infringement or Copyright piracy keeps happening each day. It is increasing. 145 Ibid 216 There is a consideration that the ineffectiveness of the enactment of Act number 12 of 1997 was because of the weakness of law enforcement practice and also substantively, the criminal charges given to the criminal of the Copyright is still too light, so then the Act was needed to be altered. The substance of the alteration of the criminal can be seen in this following matrix. Matrix 26 Alteration of Act number 12 of 1997 to Act number 19 of 2002 Regarding the Criminal Aspect Alter ed Subs tance Crim inal Aspe cts Materials of Articles of Act no. 12/1997 Alteration Material poured in Articles Act number 19 of 2002 (1) Anybody, with intention and without right announcing or duplicating a creation or provide permission for that, is charged with imprisonment at most 7 (seven) years and/or fine at most Rp. 100.000.000,(one hundred million Rupiahs) (2) Anybody with the intention to publish, exhibit, spread or sell to public a creation or work of the result of a violation of Copyright as stated in Article 1, shall be charged with imprisonment at most 5 years and/or fine at most Rp. 50.000.000,- (Fifty million rupiahs) (3) Anybody with the (1) Anybody with the intention and without right conducting action as stated in Article 2 paragraph 1 or Article 49 paragraph 1 shall be charged with imprisonment each at minimum of 1 month and/or fine at minimum for Rp. 1.000.000,or imprisonment at most 7 (seven) years and/or fine at most Rp. 5.000.000.000.(five billion rupiahs) (2) Anybody with intention to publish, exhibit, spread, or sell to public a Creation or the resulted work of Copyright or Related Right violation as stated in Article 1 shall be charged with imprisonment at most 5 years and/ or fine at most Rp. 500.000.000,- (Five hundred million rupiahs. 217 intention to violate the provision of Article 16, shall be charged with imprisonment at most 3 years and/or fine at most Rp. 25.000.000 (twenty five million rupiahs) (4) Anybody with the intention to violate the provision in Article 18, shall be charged with imprisonment at most two years and/or fine at most Rp. 12.000.000,(fifteen million rupiahs) Article 44 (3) Anybody with intention and without right duplicating the use for commercial intention of a Computer Program shall be charged with imprisonment at most 5 years and/or fine at most Rp. 500.000.000,- (five hundred million rupiahs) (4) Anybody with intention to violate Article 17 shall be charged with imprisonment at most 5 (five) years and/or fine at most Rp. 1.000.000.000,(one billion rupiahs) (5) Anybody with the intention to violate Article 19, Article 20, or Article 49 paragraph (3) shall be charged with imprisonment at most 2 (two) years and/or fine at most Rp. 150.000.000,(one hundred and fifty million rupiahs) (6) Anybody with intention and without right violating Article 24 or Article 25 shall be charged with imprisonment at most 2 years and/or fine at most Rp. 150.000.000,- (one hundred and fifty million rupiahs) (7) Anybody with intention or without right violating Article 25 shall be charged with imprisonment at most 2 years and/or fine at most Rp. 50.000.000,- (fifty 218 million rupiahs) (8) Anybody with intention and without right violating Article 27 shall be charged with imprisonment at most 2 years and/ or fine at most Rp. 50.000.000,- )one hundred and fifty million rupiahs) (9) Anybody with intention to violate Article 28 shall be charged with imprisonment at most 5 years and/or fine at most Rp. 1.500.000.000,(one billion and five hundred million rupiahs) Article 72 Sumber : Data Processed by Saidin by comparing the Act number 12 of 1997 with Act number 19 of 2002. Furthermore in the general explanation, the alteration of this Act was mentioned with the basis of thought which was as the background of the need to adjust the Indonesian Copyright Law with the results achieved in GATT Agreement 1994/WTO. The following explanation was taken from the general explanation of Act number 19 of 2002. Indonesia as island country has various richness of arts and cultures. This is in line with the various ethnics, tribes, and religion, which in whole, was a national potential that need to be protected. The richness of art and culture was one of the sources of intellectual property that can and need to be protected by law. The richness was not merely for the art and culture itself, but can be used to accelerate the ability in trade and industry which involve the Creators. By that, the richness of art and culture that is protected can accelerate the welfare, not only for the Creator, but also to the nation and the country. Indonesia has participated in the world’s society by becoming the member of Agreement Establishing the World Trade Organization, also Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, furthermore called by TRIPs, through Act number 7 of 1994. 219 Besides that, Indonesia also ratified Berne Covention for the Protection of Artistic and Literary Works through Presidential Decree number 18 of 1997 and World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty, which is called WCT, through Presidential Decree number 19 of 1997. This moment, Indonesia already had Act number 6 of 1982 regarding Copyright as altered with Act number 7 of 1987 and finally altered with Act number 12 of 1997 which furthermore called with Copyright Law. Even though it contained some of Article adjustments which in line with TRIPs, but there was still some of the things that need to be perfected to provide protection for intellectual works in Copyright, including the effort to improve the intellectual work development which derived from the various arts and cultures as mentioned above. From some conventions in Intellectual property Rights mentioned above, there were still some provisions which should have been utilized. Besides that, we need to emphasize and see the place of Copyright in one party and Related Right in another party in providing protection for certain clearer intellectual works. The explanation above became the basis to alter Copyright Law number 12 of 1997 with Copyright Law number 19 of 2002. That was realized because of the richness of art and culture, and the development of intellectual ability development of the society of Indonesia needed a fair legal protection so a good and healthy business competition vibe needed in implementing national development can be provided. Some provisions of TRIPs Agreement that transplanted into the Act number 19 of 2002 can be seen in the matrix below: Matrix 27 Transplantation of TRIPs Agreement into the Act number 19 of 2002. Article TRIPs Article 10 1. Computer programs, whether in source or object code, shall be protected as literary works under the Berne Convention (1971). 2. Compilations of data or other material, whether in machine readable or other form, which by reason of the selection or arrangement of their contents Articles of Act No. 19 Tahun 2002 Article 12 (1) In this Act, the protected Work shall be the Works in the field of science, art, and literary, which are: a. books, Computer Program, pamphlet, lay out, published written works, and all kinds of written works; b. seminar, lecture, speech, and 220 constitute intellectual creations shall be protected as such. Such protection, which shall not extend to the data or material itself, shall be without prejudice to any copyright subsisting in the data or material itself. Article 11 In respect of at least computer programs and cinematographic works, a Member shall provide authors and their successors in title the right to authorize or to prohibit the commercial rental to the public of originals or copies of their copyright works. A Member shall be excepted from this obligation in respect of cinematographic works unless such rental has led to widespread copying of such works which is materially another alike Creations; c. props made for the interest of education and science; d. songs or music with or without text; e. drama or musical drama, dance, choreography, puppetry, pantomime; f. art in any form such as painting, drawing, picture, sculpture, calligraphy, plastic art, collage and applied art; g. architecture; h. map; i. batik art; j. photography; k. cinematography; l. translation, commentary, adaptation, collected poem, database and another works resulted from adaptation. (2) Creations as stated in item f protected as its own creation without decreasing the Copyright on the real Creation. (3) the Protection as stated in Article (1) and Article (2), including all Creations which not or not yet to be published, but already in a one unity of form, which enable the Duplication of the works. Article 2 paragraph 2 (2) the Author and/or Copyright Holder on cinematography and Computer Program have the right to provide consent or prohibit anyone whom without the consent rent the Creation for commercial purpose. 221 impairing the exclusive right of reproduction conferred in that Member on authors and their successors in title. In respect of computer programs, this obligation does not apply to rentals where the program itself is not the essential object of the rental. Article 12 Whenever the term of protection of a work, other than a photographic work or a work of applied art, is calculated on a basis other than the life of a natural person, such term shall be no less than 50 years from the end of the calendar year of authorized publication, or, failing such authorized publication within 50 years from the making of the work, 50 years from the end of the calendar year of making. Article 30 and Article 29 Article 29 (1) Copyright on Creation: a. book, pamphlet, and all other written works; b. drama or musical drama, dance, choreography; c. all kinds of arts, such as painting, sculpture, and plastic art; d. batik art; e. song or music with or without text; f. architecture; g. seminar, lecture, speech and another alike Creations; h. Props; i. Maps; j. translation, commentary, quotation, and collected poems enacted as long as the Author loves and until 50 years after the Author’s death. (2) For the Creation as stated in Article (1) which possessed by 2 person or more, the Copyright enacted as long as the life of the last dead Author and enacted until the 50 years afterwards. Article 30 (1) Copyright on Creations: a. Computer Program; b. Cinematography; c. Photography; d. database; and e. Adaptation works, enacted for 222 50 years since first announced. Copyright on adaptation of written works published enacted fpr 50 years since first published. (3) Copyright on Creation as stated in paragraph (1) and paragraph (2) in this Article and Article 29 paragraph (!) possessed or held by a legal entity enacted for 50 years since first announced. (2) Article 14 1. In respect of a fixation of their performance on a phonogram, performers shall have the possibility of preventing the following acts when undertaken without their authorization: the fixation of their unfixed performance and the reproduction of such fixation. Performers shall also have the possibility of preventing the following acts when undertaken without their authorization: the broadcasting by wireless means and the communication to the public of their live performance. 2. Producers of phonograms shall enjoy the right to authorize or prohibit the direct or indirect reproduction of their phonograms. 3. Broadcasting organizations shall have the right to prohibit the following acts when undertaken without their authorization: the fixation, the reproduction of fixations, and the rebroadcasting by wireless means of broadcasts, as well as the communication to the public of television broadcasts of the same. Where Members do not grant such rights to broadcasting organizations, they Article 49 (1) Offender have the exclusive right to provide consent or prohibit another party which without the consent make, duplicate, or publish the sound recording and/or the picture performance. (2) the sound recording Producer have the exclusive right to provide consent or to prohibit another party who without the consent duplicate and/or rent the recording or sound recording. (3) The Broadcasting Institution have the exclusive right to provide consent or prohibit another party who without the consent make, duplicate, and/or re-broadcast with transmission with or without cable, or through another electromagnetic system. 223 shall provide owners of copyright in the subject matter of broadcasts with the possibility of preventing the above acts, subject to the provisions of the Berne Convention (1971). 4. The provisions of Article 11 in respect of computer programs shall apply mutatis mutandis to producers of phonograms and any other right holders in phonograms as determined in a Member’s law. If on 15 April 1994 a Member has in force a system of equitable remuneration of right holders in respect of the rental of phonograms, it may maintain such system provided that the commercial rental of phonograms is not giving rise to the material impairment of the exclusive rights of reproduction of right holders. 5. The term of the protection available under this Agreement to performers and producers of phonograms shall last at least until the end of a period of 50 years computed from the end of the calendar year in which the fixation was made or the performance took place. The term of protection granted pursuant to paragraph 3 shall last for at least 20 years from the end of the calendar year in which the broadcast took place. 6. Any Member may, in relation to the rights conferred under paragraphs 1, 2 and 3, provide for conditions, limitations, exceptions and reservations to the extent permitted by the Rome Convention. However, the provisions of Article 18 of the Berne Convention (1971) shall also apply, mutatis mutandis, to 224 the rights of performers and producers of phonograms in phonograms. Source : Data Processed by Saidin by comparing the TRIPs Argreement and Act number 19 of 2002. Copyright stands for economic rights and moral rights. Economic rights is the right to be provided by economical benefit on Creation ad related right product. Moral right is the right attached to the Author or Performer which cannot be destroyed or deleted with any reason. Even though the Copyright or Related Right had been transferred. The Copyright Protection shall not be given to an idea or suggestion because a copyrighted work have to had a typical form, personal and show its originality as a Creation born based on ability, creativity, or skill, so that the Creation can be seen, read, or heard. This Act contains some of new provisions such as: 1. Database is one of the protected Creations; 2. The use of any tools, both with cable or without cable, including internet media, to show the products of optical disk through audio media, audio-visual media and/or telecommunication tools; 3. Distpute resolution by Commercial Court, arbitration, or Alternative Dispute Resolution; 4. Temporary decree of the Court to prevent greater damage of the Right Holder; 5. The limit of processing time in the field of Copyright and Related Right, both in Commercial Court or in Supreme Court; 6. The attachment of information right of electronic management and technology control tools; 7. The attachment of supervision mechanism and protection of the products using the high-technology production tools. 8. Criminal threat on the Related Right violation; 9. Criminal threat on minimum fine; 10. Criminal threat on duplication of the use of Computer Program for commercial purpose un-legally and unlawful. Unfortunately, this alteration emphasize more on criminal aspects. As explained before, the Criminal aspects will place Indonesian society in lower rate culturally. Because only by aggravating the criminal threat, the level of obedience can be achieved. This understanding, positioned Indonesian society back to the past, 225 when humans were becoming wolf for one another such as brought forward by Thomas Hobbes. Human would prey on one another as a wolf (homo homoni lupus). To limit the action of the wolf, then a bigger legal threat is becoming one option. It seemed like the legislator still chose the option. Whereas there are another very important options which needed to be given attention more that are morality, cultural aspect, religious aspect which should have been pored in preamble of the enactment of Act number 19 od 2002. If compared with the previous Acts, the preamble of Act number 19 of 2002 was dry in philosophical values. The matrix below would clarify that kind of understanding. Matrix 28 Basis of Legislation in enacting the Act number 12 of 1997 and Act number 19 of 2002 Preamble Act No. 6/1982 a. that in the event of developmen t in law as stated in the Broadline of the Nation, (The Decree of the Representat ives number IV/MPR/19 78) also to push and protect the creation and the publication of the culture in the field of Preamble Act No. 7/1987 a. that the provided protection to Copyright basically meant as an effort to realize better vibe for the growth and development of passion to create in the field of science, art and literary; b. that in the middle of the activity in national development implementatio n which is accelerating especially in Preamble Act No. 12/1997 a. that with the acceleratin g developme nt of life, especially ij economy in national or internation al, the provided legal protection should be improved in Intellectual property Rights especially in Copyright in realizing better vibe Preamble Act No. 19/2002 a. that Indonesia is a country with various of ethnics/tri bes and culture and richness in art and literary with the developm ents which needed protection of Copyright on the Copyright ed works born from those 226 the science, art, and literary and to accelerate the developmen t of the nation intelligence in the Republic of Indonesia based on Pancasila and the Constitutio n then Copyright Law is need to be regulated; b. that based on the thing =s in item a above, then the regulation of Copyright based on Auteurswet 1912 Staadblad number 600 of 1912 need to be revoked because the inappropriat e with the science, art and literary, the violation of Copyright is also developing. Especially in criminal piracy; c. that the Copyright violation has reached a very dangerous rate and can damage the living system of society especially the passion to create; d. that to handle and stop the violation of Copyright, it is necessary to alter anand perfect some provisions in the Act number 6 of 1982 regarding Copyright; to the growth and developme nt to create in the field of science, art and literary which is very needed in the implement ation of national developme nt which goal is to create a justice, fair, developed and independen t Indonesian society inline with Pancasila and Constitutio n of 1945; b. that with the acceptance and the membershi p of Indonesia in the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property b. c. various kinds of ethnics and tribes. that Indonesia has been the member of various Interantio nal conventio ns/ agreement s in Intellectua l property Rights in common and Copyright in specific which need implement ation more in the national legal system; that the developm ent in trade, industry, and investmen t has grown so fast that need more protection on the Creator 227 need and legal goal of the nation. Rights, including Trade in Counterfeit Goods/TRI Ps which is part of the Agreement Establishin g the World Trade Organizati on bahwa dengan penerimaan as verified by the Legislation , continued with implementi ng the obligation to adjust the national legislation in the field of Intellectual Property Right including Copyright on the internation al Agreement ; c. that based on considerati on as mentioned in item a, b, and by and Related Right by paying attention on society; d. that by paying attention on experience in implement ing the existed Copyright Law, it is necessary to set the Copyright that replace the Act number 6 of 1982 regarding Copyright as altered with Act number 7 of 1987 and finally altered with Act number 12 of 1997; e. that based on considerat ion as mentioned in item a, item b, item c, and item 228 paying attention on the judging of any experience, especially the weakness of the implement ation of Copyright Law, it seems necessary to alter and perfect some provisions of Act number 6 of 1982 regarding Copyright as altered with Act number 7 of 1987 by laws. Source : d, a Copyright Law is necessary; Data Processed by Saidin by comparing the Act number 6 of 1982 with the Act number 7 of 1987, Act number 12 of 1997 and Act number 19 of 2002. Only the preamble in Act number 6 of 1982 contains the philosophical considerations. Beside referring juridically to the Constitution of 1945 also paying attention on political basis of TAP MPR Number IV/MPR/1978 which also contained the suggestion of goal of national legal development, preamble contained in the next Copyright law was dry from the philosophical values of juridical values which becoming the basis of political policy in regulating national law. The missing thing from the legislator was by putting in the provision of 229 transitional Article contained in Article 74 Act number 19 of 2002 that are: With the enactment of this Act, all legislation in the field of Copyright existed on the enactment date of this Act, shall be enforced as long as not contradicting or has not yet replaced with the new one based on this Act. And the closing provision of Article 77 Act number 19 of 2002: With the enactment of this Act, the Act number 6 of 1982 regarding Copyright as altered with Act number 7 of 1987 and last altered with Act number 12 of 1997 shall be stated as outdated. If this two Articles to be connected, then there would be two provisions enacted by now. First the Act number 19 of 2002 and second the Auteurswet 1912 Stb. No. 600. The Copyright Law resulted in independence time of Indonesia was stated to be outdated through the closing provision Article 77 Act number 19 of 2002 whereas the enactment of Auteurswet 1912 Stb No. 600 was enacted again based on the provision Article 74 Act number 19 of 2002. The Consequence was that all the preambles contained in Act number 6 of 1982, Act number 7 of 1987, or in Act number 12 of 1997 were outdated and that means the very strong philosophical basis contained in the Act number 6 of 1982 was also not to be enforced anymore. In this matter, a philosophy question occurred: what kind of philosophy that powered the national Copyright Law enforced today? If the answer is searched in Act number 19 of 2002, it will not be found. If that is the case, then it can be assured that the National Copyright Law today is an Act which no longer leave any school of thought, values, philosophical basis of Pancasila as the basis of ideology in the legislation formulation. Besides that, in the law enforcement, in the period of the enforcement of Act number 19 of 2002, it was listed that the piracy on cinematography could not be stopped even though with a severe criminal threat in the provision of the Act. In the period of 2012, according to Wihadi Wiyanto, the local recording industry has experienced disadvantage for Rp. 246,40 billion on the piracy of Digital Video Disk.146 146 Wihadi Wiyano, General Secretary of Indonesia Video Recording Association (ASI REVI), in the Tempo Newspaper on 8 March 2003. 230 The piracy on cinematography work has been in a very dangerous state, because 9 of 10 products of DVD in the market were the result of piracy which means that 90% of cinematography work spread in the market resulted by optical illegal media. This was what owned the cinematography market in Indonesia. Furthermore, Wihadi Wiyatno stated: The disadvantages value of the piracy of the film software is elevating from year to year started since 1995, that was when the Video Compact Disc product entered Indonesia. The result was, not only the film industry and video industry that experienced disadvantages but also the cinema industry because the society chose to buy pirated VCD or DVD than to watch the film in theatre. The massive piracy of VCD or DVD in or nation, made the theatre in many territories in Indonesia closed, starting with 3000 theatres to only 600 theatres. “if the pirated DVDs are as many as the pirated VCDs, it will be not impossible that there will be only 10 surviving theatres” One of the many reasons of the massive piracy of VCD and DVD was that the legal enforcer did not commit any legal action as stated in the existed Act. The Sanction brought forward to the offender was only as far as trial sanction. Legal enforcement connected with the issue of piracy in Indonesia could not be believed in, because the legal enforcer did not commit any serious legal action. Because of that ASI REVI chose to take its own step by committing campaign antipiracy to reduce the DVD piracy. 147 The piracy on cinematography work not only happened in Indonesia, but also on many territories of the world especially in Asia Pacific like India, Korea, Malaysia, and Singapore. Michael C. Ellis, the Vice President and Regional Director of Asia Pacific for Anti Piracy Motion Pictures Association Operation stated: it has been done a campaign program of anti international piracy in eight countries in Asia Pacific and has been managed to foreclose six million pieces of pirated DVD in Asia Pacific Countries (including Indonesia) or 87% of the foreclosed pirated DVD in the whole world. In 2001, they foreclosed 5 million pieces. All the pirated works was made in Asia Pacific territory, and in the other side for internal case in 147 Ibid. 231 Indonesia, Gunawan Suryomurcito concluded that the crime of piracy on cinematography works conducted in group and it cannot be detached from the factor that in both countries where the piracy conducted this whole time such as in Hong Kong and Malaysia started to tighten the legal rules regarding piracy. Gunawan Suryomurcito stated: The piracy in Indonesia was a criminal conducted in group. The Piracy in Indonesia was worse because of the condition in other countries like Hong Kong and Malaysia which tighten their legislation regarding piracy. Because of that, the pirates then moved to Indonesia and build a specific industry to produce pirated products, including DVD. The crime was conducted so organized that it was so hard to be eradicated. The weak legal enforcement became the reason of the hardship in eradicating piracy. Besides that, the existence of un-similar perception in legal enforcers and the regulation in Indonesia which was designed for law, became one of the reasons of the hardship in handling the piracy. The weakness of legal enforcement made the Copyright Holder must be active to take his own legal step. The legal enforcers themselves are still in doubt in acting proactively even though the Copyright violation was in regular criminal action. Whereas, the result of the piracy, the disadvantaged party not only the local producer who must pay the royalty to the film studio abroad, but also local producer who produce film himself in the country. This disadvantage can cause the film industry to lose investment and make the society lose their chance to have a job. Those kinds of consideration would still stain the legal enforcement of Copyright in this country. The history has listed in the enforcement time of 5 Copyright Law in this country, the aspect of Copyright violation still cannot be stopped. There must be something wrong in the choice of legal policy both in the formulation of the legislation and in the implementation. To leave the values, which was believed as the value that brought power to Indonesia, which was contained in Pancasila as the ideological basis of the formulation of the Law, was probably one reason why the legal enforcement of Copyright Law cannot be realized. The indifference of cultural values as the original paradigmatic value of Indonesia culture and society was also one factor 232 which need to be observed in the process of Copyright Law legal enforcement. G. The Period of Copyright Law Number 28 of 2014 (2014 –now) Copyright, a terminology used by the countries which adhere the Anglo Saxon legal system, auteursrechts, a terminology used by Netherlands ( a country which introduce the Continental Europe legal system in Indonesia) to stated a phrase regarding Copyright. Copyright which since the beginning introduced in Indonesian legal terminology was not a legal norm that born from the Indonesian civilization in the meaning as a product of original immaterial culture of Indonesian society. Copyright introduced today in Indonesian legal terminology was not a field that was based on the original paradigmatic values of Indonesian culture and society. Legal norms or rule recognized in Indonesian legal system today is based on foreign law. The entry of copyright law in Indonesian legal system was from Colonialism politic, that was concordance legal politic enacted by Dutch Colonialist Government by enforcing Auteurswet, contained in Staat blad number 600 of 1912 in the Dutch Indies (it was Indonesia that time, now it is called Suriname). In the journey post-independence, the regulation regarding Copyright in Indonesia refer to the choice of transplantation legal policy, that was to attach the foreign law into the law in Indonesia. That choice of legal policy often failed, both in basic policy system, and in enactment policy system. Those failure caused by a lot of factors, among others, is the basic policy system, because the legislative institution in Indonesia was failed to apply the Pancasila ideology as the basic of legal future goal in the establishment of legal norms in Indonesia. Indonesian legislative was incapable to understand legal aspiration in the meaning of law that is living in the middle of Indonesian society. The National Legislative Institution was not really undertaking its duties and functions in order to respond the folkgeist which becoming the basic (grundnorm) of the establishment of legal norms in Indonesia. This fact at last, set the legal norm of Indonesian Copyright which implemented in four times amendment of Indonesian Copyright law, to be rejected in law enforcement system or enactment policy system. It is often in the making of Copyright law, and also the other law, the process is often running on the deadline. A legislation project that has to be done in a meeting that agreed by them who sit in the 233 parliament (legislative institution). Because of that this law is seen to be forced to born. The terminology used in the law is inconsistent with scientific formulation. For instance, copyright is a work in the field of art and literature, or in the basic terminology is : scientific, artistic work, literary works 148 or in the Auteurswet terminology the terminology used were wetenschap (scientific), kunst (art) and literatuur (literary). 149 But in the Act number 28 of 2014, in the preamble in the part of preview, item b stated that “ the development of science, technology, art, and literary is so rapid that needs an uplift in the protection and guarantee of legal certainty for the Author, Copyright Holder, and Related Right owner”. In that preamble, suddenly the word “technology” was included between the word “science” and “arts and literary”. It is true that there is some progress in the field of technology, but it is not the basic of consideration to confine the copyright law, because the copyright has been limited to a scope of science, art, and literary. When the science is being applied to technology activities, then a new Intellectual Property Right that was born was patent, industrial design, variety of plants, layout design integrated circuits. The written science in the journal research report, a book that is made as reference which became a source of scientific information. If the research report, journal or book was only kept in a library or used as information source, then it is protected with Copyright. But, if the result of the research in the field of mechanic engineering which explain how to make a vehicle powered with solar system. And then that invention is implemented in technological activity and in the making of the form of the vehicle as a solar vehicle, then the invention will be protected with Copyright as Industrial Property Right that is Patent. So is when a science or a result of a research in the field of agriculture explains about the system to obtain a new variety of plant, if the research only used as information source, then the result is only protected as Copyright. But when the research is applied in technological activity of plant breeding, then the new Copyright will be 148 Berner Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, 9 September 1886 completed at Paris on May, 1896 revised at berlin on November 13, 1908, completed at Berne on March 20, 1914 and revised at Rome on June 2, 1928, at Brussels on June 1948, at Stockholm on July 14, 1967 and at Paris on July 1971, Article 2 149 Auteurswet Staatblad 1912 No. 600, 23 September 1912, Article 1 234 born, that is the protection of new Plant Variety. So is when a line, picture, color, or combination of line, picture or color poured on a paper, then it will be protected as Copyright, but if it is applied in technological activity which confine a two or three dimensional object, a new Copyright, that is Industrial Design Right is born. By that, it is not right to include the term “technology” in the preamble item b in the part of preview in Act number 28 of 2014. It proves the inconsistency and the ignorance of the legislator about copyright terminology conceptually which refer to the scientific academic basis. In the journey of the making of Copyright law number 28 of 2014, the legislators put their consideration based on the participation of Indonesian in the membership of International Convention in the field of Copyright (Berner Convention 1967, TRIPs Agreement 1994) and Related Right (Rome Convention 1961). The consideration refers to the foreign legal instrument caused the law regulation of copyright always incompatible with the development of law and the need of law by the society , because the demand of the countries in the world still want that their copyright to be protected well with Indonesian legal instrument. That is why the Indonesian Copyright law, gradually, is having alteration. That alteration, is not just about the substance, but also regarding the ideology. Even though it has been asserted that the last alteration of Copyright Law was meant to answer the mandate poured in the Indonesian Constitution of 1945, but the deviation to the Pancasila ideology is seen more. This thing can be proved from the amount of Articles contained in this Act mentioning the term “economic right”. Of course the phrase economic right was deemed to the platform of economic theories developed by Capitalist countries. The approach used in international conventions related to the copyright protection deemed to economic liberalization and it is contradicting with the economic principle of Indonesia which based on Pancasila with the platform of togetherness. Even so, the together life system in globalization era with bilateral and multilateral cooperation both in and outside of ASEAN cannot be a reason to release the constitutional responsibility by abandoning the economic values of Pancasila. However, the goal of the legislator related to the field of economic should accelerate the achievement of national future goal as mentioned in Article 27 paragraph 2 Indonesian Constitution of 1945. The cooperation in free market globalization should not be the loss of Indonesia, or the scarification of the national sovereignty by choosing 235 the basis of liberal capitalist ideology in formulating the Indonesian Copyright Law as happened in the making of Copyright law number 28 of 2014. The Copyright law should choose the sustainable paradigm which first oriented to the growth of the economic and a more equitable division from economic sources resulted from the growth to be oriented to development paradigm to accelerate the dignity of human life (Author), meaning the development is not only for the acceleration of economical value, but also to accelerate the socio-cultural value. In this perspective, the law that must be developed must contain not only “to have more” but also “to be more”. The legal development must refer to a new definition that is to accelerate the ability of the Author, because of that the making of Copyright Law is not only to fulfill the need of society in science, art and literary but also to be much further meant to achieve the right on the other Intellectual property such as patent, industrial design, new plant variety and integrated circuits which push the expansion of job opportunity. The development of Copyright law was demanded to provide pride, national glory to give sacred meaning to the nationalism in strengthening Indonesian economic with our own power and ability. By emphasizing the protection of economical right principal in the Copyright Law number 28 of 2014 means that the legislator still referred to old paradigms. It is time for the old paradigms to be abandoned which put the human as homo-economicus to homohumanus, homo- socius, homo religious and homo-magnificus. To emphasize the Copyright as economic right as regulated in Copyright Law number 28 of 2014 is to clarify the position of human as economic creature and to position ourselves as individual agent which is in the center of neoclassic economic theory (mainstream neoclassical economics) which is materialistic, without emotion, hedonestik, egoistic and rationally search for maximum economic utility which is centered to self-interest.150 This concept is growing stronger in the Act number 28 of 2014 with the Article 24 which stated: (1) Phonogram producer has economic rights. (2) Phonogram Producer economic rights referred to paragraph (1) includes the right to implement itself, give permission, or prohibit others to do: a. Duplication the Phonogram in any manner or form; 150 See further M. Teresa Lunati, Ethical Issues in Economics : From Altruism to Cooperation to Equity, Mac Millan Press, London, p. 139 – 140. 236 b. Distribution of the original or a duplicate of Phonograms; c. Rental to the public of a duplicate of Phonogram; and d. Provision on Phonogram with or without wires which is publicly accessible. (3) Distribution as referred to paragraph (2) item b, shall not apply to duplicates of fixation on performance that have been sold or that have been transferred by Producer of Phonogram to another party. (4) Every person conducting Phonogram producer economic rights referred to paragraph (2) must obtain permission from the Phonograms Producer. If in the Act number 19 of 2002 in Article 2 paragraph 2 stated: the consent only necessary for the leasehold of cinematography work and computer program but in Article 24 assert and expand the consent is required on phonogram work. The other Article such as Article 23 is also providing similar confirmation for performances work. Article 12 is for Portrait work. Beside the suppression of the Copyright as an exclusive right which consist of moral right and economic right, Act number 28 of 2014 is also contain criminal provision with a fine penalty which assert more on economic aspect that is with a fine for 1 billion, 4 billion even though the fine is defined as a maximum fine. But it can be understood that economic calculation is still made as a reference in criminal law enforcement on copyright infringement. Globalization is of course not causing Indonesia to lose its passion to fight for its national matters. Nationalism, as Sri Edi Swasono151 mentioned, is never outdated. Nationalism is still becoming the identity of each individual of Indonesia. Nationalism is national pride. A fading nationalism would fade the identity and weakening the national pride. Nationalism took its shape on various attitude and behavior. Indonesian Nationality is facing global challenge as the product of globalism. Globalism is an idealism to bear the spirit of the nation unity to maintain the togetherness in living in the world by maintaining the preservation on earth and to live together. But globalization often deviated from the pure goal of globalism. That is what happen when the countries in the world gathered in WTO which led to the ratification of General Agreement Tariff on Trade which 151 Sri Edi Swasono, Menegakkan Demokrasi Ekonomi : Globalisasi dan Sistem Ekonomi Indonesia, Scientific Oration on 62nd Dies Natalis USU, Medan, 20 August 2014 p. 20 - 21 237 contain the instrument the agreement trade related aspect of intellectual property rights which afterward become the reference for the member countries to regulate the Copyright law in each countries including Indonesia which in the field of Copyright had been amended repeatedly in order to fulfill the demand of industrial countries that powered the establishment of GATT 1994. Now Indonesia must wait and see how the Law number 28 of 2014 being enforced. H. Analysis and Invention In the time of Auteurswet 1912 was being created, there was no one that could be blamed in this Republic, since this wet was not arranged by the House of Representatives and Indonesian government, but by the Dutch colonialism government. The situation that time was so dynamic. The warriors were still preoccupied by the struggle to unite this country. The Dutch East Indies government was still believed in the effort to take control of the colony, because of that, the enactment of the origin law from their country was a good option which was already considered from the beginning. Although the manuscript of Proclamation and Constitution of Republic Indonesia implied that Indonesia had to arrange its own legal system, a legal system which is derived from the ideology of Pancasila, a legal system which is based on the original paradigmatic value of Indonesian culture and society, but the first choice of legal policy, was to continue in using the Dutch colonial law legacy. This choice of legal policy, confirmed in the Constitution of Republic Indonesia in an Article in the Transition Law, that is Article II. Whether feeling comfortable in using this law, or probably the law itself has united with this nation, or probably because of human error in forgetfulness or idleness or indifference, finally Auteurswet 1912, has been enforced for 37 years post-independence, or 70 years in total in this land of Indonesia. The desire, to possess our own copyright law, has actually appeared in 1951. It was in the second National Culture Congress in Bandung. This Congress was invented the term “Hak Cipta”. The term has been achieved, but the law is yet to be applied to replace the legacy from Dutch East Indies. The next proposal appeared when the Organization of Indonesian Authors was having suspense about the fragility in the protection of the authors’ rights. The suspense was getting worse because quantitatively, literature from Indonesian author were very few, the poorness of economical life of the authors and a low awareness on the importance of Indonesian culture. This organization 238 was also contributed in the making of copyright law manuscript, which was encouraged by the Minister of Justice in the following days. The next phase of the history was in approximately 19561959, when a council that was given a responsibility to draft the constitution, named KONSTITUANTE, was in an assembly, there was a developed idea to propose the material about copyright protection to be contained in the constitution. But before the proposal was completed, the council of Konstituante was being dismissed when the Presidential Decree was published on 5th July 1959. 18th December 1958, was the reign of piracy in copyrights and book publishing. Until finally the organizations which related to the world of authors and publishing, which were united in assembly deliberation of literature (Majelis Musyawarah Lektur) which consisted of; OPI, GN, PTBI, GIBI, and IKAPI, published a statement and declaimed all kinds of copyrights piracy. Although there was no effect from that movement, but the history recorded that the movement has already given a sufficient influence and contribution in the making of copyright law manuscript in the following days. Whether what atmosphere was in Indonesian political world after the year of 1958, it can be assured that Indonesia signed out from the membership of Bern Convention, a convention that gave a copyright protection for its members. The reason was, Indonesian membership that time, was the continuance of Dutch membership in that convention. Politically, Indonesia wanted to let all of the Dutch political hegemony go, in connection with the return of West Irian. Juanda, who led the ministry cabinet that time, decided to sign out from Bern Convention, to expedite the diplomacy to the return of West Papua policy. Because of that, the effort to have an original Indonesian copyright law was in a long vacuum since 1958 until 1972. Such a long period of time wasted. After that time, a new consideration to make a copyright law which had been dreamt by the people of this nation appeared. IKAPI, in 1972, formed a committee, to draft the copyright law. There were three reasons that IKAPI took this step. First, quantitatively, piracy was getting worse. Second, the rule of law in the meaning of Auteurswet 1912’s substance, could not afford protection, third, law enforcement and legal culture of the society could not give a favorable condition for the protection of authors and publishers. Finally IKAPI arrived at one desire to end the domination of Auteurswet 1912, which was the product of colonialism, with the hope to the existence of ne law that is suitable for an independence country which was just been 239 freed from colonial domination. The manuscript which was proposed by IKAPI was known with the manuscript of copyright law IKAPI 1972. This manuscript of copyright law IKAPI 1972 was not just born like that. It was born from scientific, academic activities which were done by IKAPI from 1966 to 1968. Even this manuscript was not accommodated by the government and the house of legislative body to be discussed in the completing process to become a copyright law. After 1972, there were still a lot of activities to make the draft of national copyright law. In 1973, Department of Information organized a workshop about copyright, followed by Agency for National Legal Development, which was under the authority of Department of Justice, cooperated with Law faculty of Universitas Udhayana, in 1975, held meeting which specifically discussed about copyright law in order to make it useful in the making of copyright law. In 1976, the Minister of Justice, formed a committee from each department from Department of Information, Department of Education and Culture, Department of Finance, the Supreme Justice, Attorney General, National Institute of Science, and the Department of Justice to draft the copyright law. Finally in 1977, after a hard work for one year, the committee was managed to draft the copyright law. Although the draft had been done in 1977, this country must wait for 5 years in hoping for the enactment of the law. Through presidential mandate on 12th January 1982 Number R.02/0.U/I/1982 the draft of law was proposed to the House of Representatives of Republic of Indonesia. Implicitly, it can be concluded that the will to transform the Auteurswet 1912 Stb. No. 600 ideologically and philosophically, was mentioned in the government statement in front of the plenary assembly of House of Representative, which was, this copyright law, in the future, has to adhere the negotiation for consensus principle, the balance in personal and community interest principle, justice principle, and legal protection principle. These principles were the embodiment from the basic of ideological philosophy of Pancasila. In this law, is also adhere the dynamic principle, that nothing is fixed, everything will change, because of that, this law put the aspect of the development of science and technology. But the content of the law was all locked with the Indonesian Identity principle (the original paradigmatic value of Indonesian culture and society). This is a new phase in the history of the establishment of copyright law which answered the future goals and mandate of the 240 people of Indonesia, in connection with what is contained in TAP MPR NO.IV/MPR/1978 about the State Policy Guidelines, which require a legal reform in the national development of law. A law that refers to the national system of Indonesia, basic ideology/philosophy of Pancasila, derived from the original paradigmatic value of Indonesian culture and society. The vigor in renewal, the courage to put national identity into the legal norms, but still respect and appreciate the rights of other people and to run the social function as ordered by Pancasila that there is no such thing as an absolute right, everything has its limit, this is what is so called as social function. That was a remarkable event of history which must be memorized when Act Number 6 of 1982 was born. There were many events recorded. But the memory of Indonesian people is a short-term memory, and when the history began to be vague, that was when capitalist countries started to obtrude. It is right that recorded history from the memory is not a neutral action to maintain and neglect and finally the contention will leave a social and cultural consequences. There was not any radical legal policy movement that objected the entry of liberal capitalist concept towards the Act Number 6 of 1982, followed by four transformation of copyright law, until the existence of the Act Number 28 of 2014. The choice of the national copyright law legal transplants was stained by political dynamics in a long period of time since 1912 until 2012. This 100 years period of the enactment of copyright law in Indonesia shows us the political side with the dynamics, each in every phase or period of history based on the enactment of this law. Half hearted legal policy, was also stained the phases of history of the development of copyright law. Even sometimes, it was obvious that an ambivalent two-faced legal policy appeared when facing the pressure from foreign countries especially after the ratification of WTO/TRIPs Agreement 1994. The contention of Pancasila ideology versus liberal-capitalist ideology was very real and consciously or not, was stained the national copyright law in Indonesia which normatively contained in the last two laws which was, and is enforced in this country. In the practice of national legislation, except in the arrangement of Act Number 6 of 1982, there was never a consistency of maintaining the ideology of Pancasila. A choice of pragmatist legal policy from time to time, has become a real legislative’s choice in producing national copyright law. 241 Legal transplant legal policy was systematically designed since the beginning of Dutch colonialism and continued consciously in independence time and also in globalization era with all the dynamics. The dynamics of copyright law legal transplants policy in this country showed a varied political choice in each phases of history. In the time of Dutch East Indies, to equalize the enforcement of copyright law in Netherlands with its colony by publishing the Auteurswet 1912 Number 600, was enforced for 70 years through the concordance legal policy. The next phase was on post-independence from Dutch colonialism, after 37 years of the enactment of Auteurswet 1912 Stb. No 600, Indonesia asserted that ideologically / philosophically, Auteurswet 1912 Stb No. 600 did not compatible with future goals of Indonesian National law, so that this wet had to be revoked, along with the birth of Act Number 6 of 1982, which law was only enforced five years through legal transplants policy. The hustle and bustle along with various allegations towards Indonesia from foreign countries as a pirate of foreign copyrighted works country, with the pressure that Indonesia must accept the ideas and notions from foreign countries, ended with the revision of the five years old law, followed by the birth of Act Number 7 of 1987 through pragmatist legal policy. After seven years enforcement of this law, on 15 th April 1994 in Morocco, Indonesia ratified the Agreement Establishing the World Trade Organization, with all the attachments, one of them is the TRIPs Agreement which is mainly contained with liberal-capitalist ideology / philosophy. Three years after the ratification of TRIPs Agreement, Indonesia once again transformed its copyright law on 1997, with Act Number 12 of 1997 with pragmatist and legal transplants policies. It looks like this country must learn to review the history. How come this country had five different copyright laws in one hundred years (one of them was the legal product from Dutch East Indies) and none showed a well-compatible sides, each from substance and the application of the law. That is why the legal approach from historical study needs a special concern in the curriculum of legal study. This kind of approach is not only meant for us to look back into the existence of law in the past, but also to be made as a study in order to arrange the steps or strategies on legal policy which will be developed in the future. 242 BAB III POLITIK HUKUM : PERGESERAN NILAI FILOSOFIS A. Pengantar Perubahan dan pergeseran nilai filosofis, itulah kata yang tepat untuk merumuskan ideologi sebagai landasan filosofis pembentukan sebuah undang-undang dalam satu negara, tapi kemudian substansi undang-undangnya tidak mencerminkan ideologi yang telah disepakati sebagai dasar berdirinya negara tersebut. Ada nilai yang masih mencerminkan akar budaya masyarakatnya namun ada yang tercerabut dari akarnya. Akar budaya, akar kultural, akar sosiologis yang membentuk peradaban hukum. Tercerabut karena peradaban hukum itu dibangun tidak lagi berdasarkan the original paradigmatic value of Indonesian culture and society akan tetapi dibangun dengan nilai yang dianut oleh bangsa lain, oleh peradaban lain, oleh nilai sosio-kultural bangsa lain. Paling tidak, dalam penyusunan undang-undang hak cipta nasional, terdapat lima nilai filosofis Pancasila yang berubah dan bergeser, dalam takarannya masing-masing. Kelima nilai itu sesuai dengan lima sila yang disepakati sebagai dasar filosofis penyusunan undang-undang dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Pertama, nilai Ketuhanan, penempatan nilai Ketuhanan dalam sila pertama bukanlah sesuatu yang dilakukan tanpa alasan oleh pendiri bangsa ini. Menempatkan dasar pertama Pancasila dengan meletakkan nilai Ketuhanan dalam sila pertama, didahului oleh berbagai argumentasi dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tatanan nilai ini semestinya kelak terjelma dalam peraturan perundangundangan Indonesia termasuk hak cipta. Kedua, nilai filosofis kemanusiaan, bahwa semua aktivitas legislasi harus bersumber pada nilai kemanusiaan, tidak boleh bergeser ke nilai kebendaan atau materialis yang mengukur semua aktivitas dengan benda yang bernilai ekonomis, termasuk dalam melahirkan undang-undang Hak Cipta Nasional. Ketiga, nilai kebangsaan atau nasionalitas, nilai ini merupakan nilai keberpihakan Undang-undang Hak Cipta Nasional pada kepentingan nasional. Nilai kesatuan dan sederajat. Dalam aktivitas penyelenggaraan negara serta memahami berbagai hal haruslah ditempatkan dalam satu wadah kesatuan yang utuh dan sederjat. Tidak ada yang satu lebih utama dari yang lainnya. Bahwa fungsi dan peranan 243 masing-masing lembaga itu berbeda, namun dalam tugasnya adalah untuk mewujudkan satu tujuan bersama. Tidak boleh terjadi egosentris, egosektoral atau ego institusinal. Semua bekerja dalam satu kerangka sistem yang disebut sebagai sistem nasional. Terlebih lagi dalam pekerjaan legislasi dan memahami sebuah kehendak rakyat, semuanya harus dilakukan dengan pendekatan sistem. Nilai kebangsaan yang di dalamnya tersirat bahwa keutamaan melindungi kepentingan nasional, ketika memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya. Lebih dari itu juga warga negaranya harus mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan dirinya dan melahirkan kreativitas guna memajukan perdaban bangsanya. Negara harus diberikan kedudukan yang kuat ketika berhadapan dengan negara lain. Nilai kebangsaan harus dijadikan sebagai spirit guna mengatasi gerakan imperialis tersembunyi dengan cara-cara lain, misalnya melalui bangtuan pinjaman luar negeri atau dengan menggunakan instrumen hukum Internasional. Keempat, adalah nilai musyawarah, mufakat dan kekeluargaan. Nilai-nilai ini hendaknya sudah tercermin dalam tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bumi Indonesia baik itu merupakan produk legislatif dalam bentuk undang-undang termasuk Undang-undang Hak Cipta Nasional. Nilai kekeluargaan yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai yang dihadapkan dengan nilai indivudualis. Nilai kekeluargaan ini adalah nilai yang tertanam sejak lama dalam masyarakat Indonesia, yang menjadi pembeda masyarakat Indonesia dengan masyarakat yang hidup di belahan bumi Barat. Musyawarah dan mufakat dapat dijadikan penangkal bagi masuknya nilai-nilai demokrasi liberal. Kelima, nilai keadilan dan kesejahteraan harus tercermin dalam norma hukum undang-undang hak cipta nasional yang dihadapkan dengan nilai-nilai kapitalis dan liberal. Kesejahteraan masyarakat Indonesia yang mengacu pada kesejahteraan sosial berbeda dengan konsep negara kesejahteraan dengan latar belakang kapitalis. Jika sila dari Pancasila itu hendak diletakkan dalam tataran filosofis dalam pemebentukan tata (sistem) hukum, maka dengan meminjam kerangka teori Hans Kelsen, Pancasila itu dapat ditempatkan sebagai grundnorm (norma dasar) yang merupakan syarat transendental logis bagi berlakunya seluruh tata hukum dalam satu negara. Selanjutnya menurut Kelsen, jika hukum telah menentukan pola prilaku tertentu, maka setiap orang seharusnya berperilaku sesuai pola yang ditentukan itu. Orang harus menyesuaikan diri dengan apa yang telah 244 ditentukan dan itulah sifat normatif dari hukum. 152 Kelsen sendiri tidak menyebut apa yang menjadi isi Grundnorm itu. Akan tetapi ia menyebutkan, seluruh tata hukum positif harus berpedoman secara hirarki pada grundnorm itu. Jadi dapat dipastikan bahwa Kelsen membuat tingkatan anak tangga secara hirarki tentang keberlakuan tertib hukum. Grundnorm itu bermuatan nilai-nilai yang sangat abstrak. Jika nilai-nilai yang abstrak itu diturunkan maka ia akan memunculkan tata nilai (asas-asas), yang juga berifat abstrak. Ia baru tampak nyata dalam wujud tingkah laku (hukum) masyarakat. Dalam hubungannya dengan Pancasila, maka posisinya dalam kerangka teori Hans Kelsen adalah sebagai grundnorm. Mahadi 153 mencoba untuk melukiskan teori Kelsen itu dalam hubungannya dengan Pancasila sebai grundnorm dan sampai pada tataran tingkah laku sebagai berikut : Pancasila Tingkah laku hukum Gambaran di atas menurut Mahadi adalah jarak yang sangat sederhana, yakni mulai dari yang abstrak (nilai-nilai Pancasila) sampai pada yang konkrit (tingkah laku hukum). Akan tetapi diantara jarak itu, dapat diselitkan anak tangga yang menggambarkan berbagai jarak, mulai dari Grundnorm yang abstrak sampai pada tingkah laku hukum yang konkrit. Susunan anak tangga itu digambarkan oleh Mahadi sebagai berikut : 152 Lebih lanjut lihat Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal 127. Lihat juga Hans Kelsen, Essays in Legal and Moral Philosophy Hukum dan Logika (Terjemahan B. Arief Sidharta), Alumni, Bandung, 2006. Hans Kelsen, Dasar-dasar Hukum Normatif Prinsip-prinsip Teoretis Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Hukum dan Politik, (Terjemahan Nurulita Yusron), Nusa Media, Bandung, 2009. Lihat juga Jimly Asshiddiqie, dan M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006. Bandingkan juga dengan H.R. Otje Salman S, dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Refika Aditama, Bandung, 2008. Lihat lebih lanjut Adnan Buyung Nasution, Demokrasi Konstitusional, Kompas, Jakarta, 2011. 153 Lihat lebih lanjut Mahadi, Falsafah Hukum Suatu Pengantar, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989. 245 Pancasila 1 2 3 Tata nilai (asas-asas) Tata Norma Norma hukum positif Tingkah laku hukum Urutannya dalam Pancasila sebagai grundnorm (lantai puncak) , diturunkan ke anak tangga pertama berupa tata nilai (dalam bentuk asas-asas hukum), kemudian diturunkan ke anak tangga kedua berupa tata norma, selanjutnya dari situ diturunkan ke anak tangga ke tiga berupa norma hukum positif. Setelah itu norma hukum positif dijadikan sebagai dasar (lantai dasar) pedoman untuk bertingkah laku (tingkah laku hukum) yang wujudnya sudah terlihat konkrit. Kembali ke Teori Kelsen, maka tujuan utamanya adalah untuk menjawab, apakah hukum itu dan bagaimana hukum itu dibuat? Bukan pertanyaan apakah hukum yang seharusnya (what the law ougth to be) atau bagaimana seharusnya hukum dibuat (ought to be made). Itulah konsekuensi dalam satu negara ketika memilih Ideologi yang diletakkan sebagai Grundnorm. Ketika Pancasila dipilih sebagai dasar negara, sumber dari cita-cita hukum nasional maka semua undang-undang yang lahir haruslah didasarkan pada landasan filosofis Pancasila, sebagai grundnorm. Sebagai ideologi Negara yang telah dipilih dan ditetapkan sebagai sumber dari segala sumber hukum maka pilihan politik hukum haruslah mengacu pada Pancasila sebagai landasan filosofis. 154 Sistem 154 Ada tiga landasan yang harus diperhatikan dalam pembuatan undangundang (semua peraturan perundang-undangan) yakni landasan filosofis yaitu ideologi Pancasila, landasan yuridis atau landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 dan landasan operasional yaitu Garis-Garis Besar Haluan Negara atau saat ini berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Tiga landasan tersebut oleh Solly Lubis disebutnya pertama sebagai landasan ideal sistem nasional, kedua landasan 246 hukum nasional dalam berbagai pengertian haruslah memiliki karakteristik yang bersumber pada ideologi Pancasila. Inilah yang oleh Satjipto Rahardjo disebutnya sebagai sistem hukum Pancasila. 155 Sebagai sebuah negara yang telah memiliki sistem hukum sendiri sebelum sistem hukum nasional yang mengacu pada landasan ideologi Pancasila dirumuskan, 156 sudah barang tentu hal ini akan mempengaruhi arah dan jalannya politik hukum nasional. Di satu sisi,hukum yang dibangun harus mengacu pada landasan ideologi Pancasila di sisi lain telah ada hukum yang berlaku yang berlandaskan ideologi “Barat” baik karena peninggalan Hukum Kolonial maupun karena pengaruh perkembangan peradaban modern dalam pergaulan struktural sistem nasional dan ketiga landasan operasional sistem nasional. Lebih lanjut lihat M. Solly Lubis, Sistem Nasional, Mandar Maju, Bandung, 2002. 155 Lihat lebih lanjut Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas Jakarta, 2003, hal. 10. Pengertian sistem hukum Pancasila dimaksudkan sebagai wadah untuk menerima seluruh nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia yakni nilai-nilai yang bersumber dari akar budaya hukum Indonesia seperti nilai kekeluargaan, nilai kebapakan (pathernalistik) nilai keserasian dan keseimbangan dan nilai musyawarah. Nilai-nilai ini sangat berbeda dengan sistem formal yang dipakai dan didominasi oleh legalisme liberal yang dikemudian hari inilah yang akan menimbulkan persoalan tersendiri ketika norma hukum itu diterapkan. Hukum yang dibentuk atau terbentuk yang mengacu pada sistem hukum kapitalis dan liberal yang kemudian disusun menurut tata hukum yang berlaku di Indonesia baik itu dari cara pengusulan dan pengajuannya pada tahap awal maupun pada saat proses kelahirannya hingga akhirnya disahkan sebagai undang-undang lalu kemudian diberlakukan untuk mengikat seluruh anggota masyarakat. Padahal masih ada konflik yang tersisa di dalamnya yakni konflik ideologi yang mau tidak mau membuat hukum itu menjadi tertolak ketika diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Ada kesan seolah-olah rule of law tidak tegak di Indonesia, padahal terjadi kesenjangan antara rule of law dengan struktur sosial kultural masyarakatnya. Nilai kekeluargaan, nilai kebapakan dan nilai musyawarah tidaklah dapat berterima begitu saja dalam proses penegakan hukum (law enforcement . Satjipto Rahardjo melihat persoalan kesenjangan ini tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga terjadi di kawasan Asia Timur, Korea, Jepang dan Thailand. 156 Sebelum Indonesia merumuskan sistem hukum nasionalnya sendiri, Negeri ini telah memiliki sistem hukum yang plural yakni sistem hukum adat, sistem hukum kebiasaan, sistem hukum Islam. Lihat lebih lanjut Sayuti Thalib, Politik Hukum Baru, Mengenai Kedudukan dan Peranan Hukum Adat dan Hukum Islam Dalam Pembinaan Hukum Nasional, Bina Cipta, Jakarta, 1986. Disamping itu pada masa Kolonial Belanda, wilayah jajahan ini juga berdasarkan asas konkordansi diberlakukan hukum kolonial : mulai dari hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana sampai pada hukum acara perdata dan hukum acara pidana serta bidang-bidang hukum yang tersebar secara sporadic termasuk hukum yang mengatur tentang hak cipta yakni Auteurswet 1912 Stb No. 600. Soetandyo Wignjosoebroto, melukiskan secara baik tentng bagaimana dikemudian hari hukum Kolonial itu seperti air mengalir perlahan tapi pasti kemuian diterima menjadi hukum nasional. Baca lebih lanjut, Soetandyo Wignjosoebroto, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hal. 19. 247 anatara bangsa di era globalisasi. Perjalanan bangsa-bangsa di dunia sebagai akibat pergaulan antar bangsa dan didorong oleh kemajuan teknologi informasi dan transportasi serta kemajuan dalam bidang industri yang diikuti dengan berobahnya pola-pola perdagangan jasa dan barang, semua ini berakibat Indonesia harus mengikuti pola perubahan yang terjadi dalam arus tatanan dunia yang sedang berobah tersebut yang berdampak pada pilihan politik hukumnya. Pergeseran nilai tidak bisa lagi dihindari baik itu terjadi secara alami atau terjadi secara sadar. Pergeseran nilai itu menyebabkan nilai-nilai yang ada atau nilai-nilai sebelumnya menjadi ditinggalkan digantikan dengan nilai yang baru. Berbeda dengan perkembangan nilai, nilai yang ada sebelumnya masih ada namun dikembangkan atau diperbaharui sesuai dengan tuntutan zaman. Tak pelak lagi ketika undang-undang hak cipta nasional (mulai dari Auteurswet 1912 sampai dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2002) semuanya bernunasa pergeseran dari nilai Pancasila ke nilai kapitalis liberal. Bukan perubahan, sebab jika perubahan yang terjadi maka, nilai-nilai yang telah ada tetap dijadikan dasar dalam pembentukan hukum nasional atau dalam kasus ini adalah undangundang hak cipta nasional. Begitu kental terasa pergeseran nilai itu, ketika Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 19 Tahun 2002 menekankan perlunya izin dari pemegang hak cipta untuk menyewakan hak cipta karya sinematografi. Jika seseorang membeli kepingan VCD atau DVD untuk kemudian digunakan sebagai salah satu instrumen untuk usaha “Cinema Keluarga” yang bersangkutan harus memohon izin dari pemilik hak cipta sinematografi. Padahal yang disewakan adalah hak untuk menikmati hasil karya cipta tersebut, bukan memperbanyak atau memproduksi kepingingan VCD atau DVD yang baru. Sangat kapitalis rumusan Pasal 2 ayat (2) ini yang berbeda dengan ketika seseorang membeli mobil lalu kemudian mobil itu ia sewakan dengan pihak ketiga. Hubungan hukum seperti ini tidak diharuskan meminta izin dari perusahaan otomotif yang memproduksi mobil tersebut. Adalah berbeda ketika seseorang itu mendirikan industri otomotif yang meniru dari desain produksi, meniru seluruh perangkat lunak yang ada pada mobil tersebut, yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak kekayaan intelektual. Di sinilah perbedaan yang sangat tajam antara landasan ideologi Pancasila dengan ideologi liberal kapitalis. Hal yang tidak patut untuk dilindungi kemudian menjadi sebuah keharusan untuk diproteksi demi melindungi 248 hak (kapital atau property) para pencipta atau para pemegang hak cipta. 157 Pergeseran itu tidak serta merta terjadi dengan sendirinya, tapi terjadi dengan (atau tanpa) disadari oleh pelaku yang memiliki kompetensi untuk itu di Republik ini. Legislatif adalah garda terdepan yang menggiring terjadinya pergeseran itu. Pilihan para politisi di Republik ini sejak awal tidak didasarkan pada sebuah cita-cita murni untuk mewujudkan tujuan negara yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa ini dan diabadikan dalam Pembukaan UUD 1945. Para politisi bangsa ini sedikit sekali yang tampil sebaga negarawan atau tehnokrat. Banyak catatan para politisi yang berpandangan pragmatis, hingga akhirnya banyak sebutan untuk mereka, mulai dari politisi karbitan sampai pada politisi kutu loncat. Ini semua merupakan ungkapan yang memperlihatkan betapa cita-cita bangsa ini tidak akan terhela dengan lokomotif politisi yang seperti itu. Tak jarang kewenangan politisi yang duduk di lembaga legislatif yang memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang akan tetapi dalam kasus penyusunan undang-undang hak cipta nasional lebih banyak bernuansa menyahuti keinginan eksekutif. Mulai dari inisiatif pengusulan rancangan undang-undangnya sampai pada pengumpulan informasi dan sosialisasi rancangan undang-undangnya. Dalam kasus melahirkan undang-undang hak cipta nasional (sebut saja mulai dari Undangundang No. 6 Tahun 1982 sampai dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2002) pihak eksekutif terus menerus memotori untuk kelahiran undang-undang tersebut. Ini menimbulkan kesan bukan saja memposisikan legislatif pada kedudukan yang tidak berdaya akan tetapi lebih jauh posisi legislatif dalam melahirkan undang-undang hak cipta nasional hanya tampil sebagai lembaga justifikasi dalam arti “lembaga pembuat stempel” sebab legislatif hanya tampil “di penghujung” atau di 157 Sayangnya tidak semua manfaat dari perlindungan seperti itu dinikmati oleh penciptanya. Yang lebih banyak menikmati adalah para produser dan distributor dari hasil karya sinematografi tersebut. Tanpa disadari norma itu hanya membuahkan keuntungan yang besar bagi para pelaku bisnis di bidang karya sinematografi. Para produser dan distributor menjadi kaya raya di satu sisi namun di sisi lain para aktor, para penulis naskah seringkali jatuh dalam dunia kemelaratan. Inilah buah dari ideologi kapitalis yang oleh Joost Smiers Marieke Van Schijndel, menyarankan agar diatur kembali mengenai proteksi terhadap hak cipta. Bagaimana para seniman film yang tak terhitung jumlahnya bisa menjual karya mereka dan mendapatkan kehidupan yang layak, Lihat lebih lanjut, Joost Smiers Marieke Van Schijndel, Imagine There is No Copyright and No Cultural Conglomerates Too : An Essay (Amsterdam : Institute of Network Cultures, 2009) Terjemahan Hastini Sabarita, Dunia Tanpa Hak Cipta, Penerbit Insist Press, Jakarta, 2012, hal. 153-154. 249 saat-saat akhir undang-undang itu disahkan yakni pada saat pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat. Hasilnya adalah muatan undang-undang itu lebih bernuansa keinginan eksekutif daripada nuansa keingian rakyat. Jika dominasi eksekutif menjadi lebih besar dalam muatanmuatan undang-undang yang diberlakukan, maka sesungguhnya hal itu akan menyisakan diskusi bahwa secara substansi undang-undang itu telah memuat dan menempatkan “spirit” kekuasaan di dalamnya. Lebih lanjut hal ini akan menyebabkan konsep negara hukum akan bergeser menjadi negara kekuasaan. Semula gagasan negara hukum (rechtsstaat) bergeser pemaknaannya menjadi negara kekuasaan (machtsstaat). Eksekutif semakin gemilang merumuskan dan menjalankan aktivitas operasional penyelenggaraan negara. Kekuasaan eksekutif menjadi sangat “gemuk” sebaliknya kekuasaan legislatif menjadi “kurus”. Kewenangan untuk membuat undang-undang tidak lebih dari upaya menjastifikasi keinginan eksekutif. Dampaknya adalah semakin besar kewenangan eksekutif, maka semakin besar potensi negeri ini menjadi negara kekuasaan. 158 Ketika kekuasaan diletakkan di atas segalanya, maka potensi kemanusiaan semakin terancam. Dehumanisasi hukum, itulah yang terjadi di kemudian hari. Memimpin dan menyelenggarakan aktivitas kenegaraan dengan pendekatan kekuasaan selalu dibayar dengan harga mahal. Sebuah harga adalah sebuah nilai ekonomis dan nilai spiritual. Ada kalanya nilai ekonomis di kedepankan dan ini berdampak pada nilai materialis dan hedonisme. Kondisi ini tak pelak lagi telah menjadi warna baru dalam peradaban bangsa ini pada tataran hari ini. Nilai spiritual yang selama ini berpangkal pada nilai religius telah tumbuh dan berkembang lalu bergeser menjadi nilai materialis. Sebuah 158 Pada masa undang-undang hak cipta nasional dilahirkan, kekuasaan presiden (baca : eksekutif) dalam membentuk undang-undang begitu kuat. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan : Presiden memegang kekuasaan undangundang dengan persetujuan DPR. Pasal 20 ayat (1) menyatakan : tiap undang-undang menghendaki persetujuan DPR. Setelah diamandemen presiden hanya diberi hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR sedangkan DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Singkatnya, hasil amandemen UUD 1945 mendesain proses pembentukan undang-undang yang secara ekstrim berbeda yang semula kekuasaannya di tangan presiden tetapi kini terletak di genggaman DPR. Lihat lebih lanjut, Muhammad Mahfud MD, ketika mengantar karya disertasi Pataniari Siahaan, yang kemudian dibukukan. Lebih lanjut baca, Pataniari Siahaan, Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Pasca Amandemen UUD 1945, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hal. xiv-xv. 250 kepuasan spiritual dalam kehidupan seperti kebahagiaan, kedamaianan dan kenyamanan akhirnya takluk dengan nilai material. Tragis dalam sebuah negara yang tumbuh bersahaja, dengan alam yang bersahabat, penduduk yang ramah, sepi dari caci maki namun berubah menjadi bangsa yang rakus, beringas, mengambil dari alam lebih dari yang seharusnya. Esploitasi terhadap sumber daya alam secara berlebihan tanpa memperhitungkan kemampuan daya dukung lingkungan, tanpa memperdulikan atau memikirkan bahwa di bumi pertiwi ini masih akan ada generasi mendatang yang menggantungkan hidupnya dengan alam dan lingkungan sekitar. Masyarakat manusia di bumi pertiwi ini adalah satu keluarga besar yang terikat dalam satu nation, sebuah keluarga yang disebut Indonesia. Akan tetapi dalam banyak kasus nilai kekeluargaan itu telah bergeser menjadi nilai individualis. Sikap masyarakat yang cenderung selama berabad-abad menunjukkan kepatuhan terhadap pemimpin, kepatuhan terhadap guru, kepatuhan terhadap adat istiadat bergeser menjadi terang-terangan menunjukkan sikap perlawanan. Nilai protogonis (kepatuhan) telah bergeser menjadi nilai antagonis (pembangkangan). Sikap egoinstitusional dan egosektoral, semakin mengukuhkan pandangan bahwa berfikir secara sistemik bukan lagi dianggap sebagai cara berfikir benar untuk menyelesaikan berbagai problem bangsa. Akibatnya posisi negara semakin hari semakin melemah. Kepercayaan masyakat kepada institusi pemerintah semakin hari semakin terkikis. Yang kuat selalu saja memenangkan pertarungan (apa saja) ketika berhadapan dengan pihak yang lemah. Sedemikian jauh dampak dari pilihan politik transplantasi hukum asing ke dalam hukum nasional, jika tidak disaring dengan ideologi dan dasar filosofis negara. Liar, itulah julukan untuk sebuah kekuasaan politik yang tidak dibatasi oleh hukum yang berfondamen kepada the original paradigmatic value of Indonesian culture and society. Kapitalis liberal sedang menanti di hadapan bangsa ini. Imperialism tidak dapat lagi hidup di era Pasaca Peranga Dunia II seperti yang terjadi pada masa lalu. Akan tetapi imperialism tetap akan ada, namun wujudnya berubah. Imperialism tidak lagi dalam bentuk koloni atau aneksasi terhadap wilayah negara lain, dengan menggunakan alat atau mesin perang, akan tetapi berubah dalam bentuk penciptaan proses ketergantgungan secara ekonomi dan politik. Secara ekonomi penjajahan itu dilakukan melalui bantuan pinjaman di lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Worl Bank. Penjajahan berikutnya adalah menggunakan instrumen hukum Internasional dan badan-badan Internasional di mana Indonesia menjadi 251 anggotanya. Penjajahan yang terselubung itu pada akhirnya merambah juga ke ranah hukum dengan mengharuskan Indonesia menyesuaikan peraturan perundang-undangannya dengan Instrumen hukum internasional yang berlatar belakang ideologi kapitalis, itulah wujud nyata ratifikasi hasil kesepakatan GATT/WTO 1994 yang di dalamnya memuat TRIPs Agreement. Sebuah kesepakatan yang mengharuskan Indonesia untuk menyesuaikan peraturan atau Undang-undang HKI-nya termasuk di dalam Undang-undang Hak Cipta dengan TRIPs Agreement tersebut. Kesepakatan yang menjadi dasar nundang-undang yang seharusnya mengacu pada landasan filosofis-ideologi Pacasila grundnorm yang dimaksudkan untuk menguatkan jati diri dan posisi bangsa bergeser menjadi melemahkan posisi negara. Kedaulatan negara merdeka bergeser menjadi kedaulatan imperialis terselubung. Undang-undang hak cipta nasional yang seharusnya memuat nilai-nilai yang berisikan aspirasi dan kehendak rakyat yang tercermin dalam Pancasila sebagai landasan ideologi negara, grundnorm, sumber dari sumber tertib hukum kemudian bergeser ke ideologi kapitalis, dan wujud normatif yang terlihat dalam undang-undang hak cipta nasional adalah cerminan dari ideologi kapitalis itu. 159 Memasuki era globalisasi, itu berarti membawa gerbong negara ke dalam dunia global tanpa batasan dinding-dinding atau sekatan nasional. Perundingan Uruguay Round misalnya, yang semula dimaksudkan untuk menangani masalah perdagangan internasional secara integratif namun kemudian telah menggelindingkan berbagai issu-issu lain diantaranya adalah tentang perlindungan hak kekayaan intelektual. Banyak pertimbangan yang dilakukan Indonesia pada saat memasuki perundingan Uruguay Round antara lain : keterkaitan sektor perdagangan dalam negeri dengan sektor perdagangan luar negeri. Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan pertumbuhan ekonominya melalui sektor migas, karena itu harus beralih kepada eksport non 159 Paling tidak, inilah yang disinyalir oleh Mahfud MD bahwa banyak undang-undang yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan penyelenggara negara di luar amanat eksplisit konstitusi dan di luar kebutuhan dan keinginan masyarakat dan bahkan menyimpang secara ideologis. Untuk itulah pembentukan hukum (dalam arti undangundang) atau legislasi, menjadi sangat penting dan sangkin pentingnya Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa pembentukan hukum itu awal dari sekalian proses pengaturan masyrakat, sebagai pemisah keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum. Lebih lanjut T. Koopman, mengatakan tujuan utama legislasi bukan sekedar menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat, akan tetapi lebih jauh untuk menciptakan modifikasi dalam kehidupan masyarakat. Lihat lebih lanjut Patiniari Siahaan, Ibid, hal. xiv. 252 migas, dan ini menyebabkan Indonesia harus menyesuaikan serangkaian langkah deregulasi dan debirokratisasi. Sedangkan dari aspek luar negeri pengamanan eksport non migas tergantung pula dari keterbukaan pasar internasional.160 Disinilah bertemunya faktor luar negeri (asing) dengan faktor dalam negeri (values of Indonesia). Nilainilai ke-Indonesia-an menjadi harus bergeser dan pergeseran yang lebih jauh akan mengarah pada nilai kapitalis-liberal yang ditawarkan oleh sistem perdagangan dunia yang serba terbuka itu. Meskipun bidang perdagangan ini merupakan lapangan hukum netral dalam arti tidak berhubungan erat dengan aspek budaya dalam arti sempit dan aspek religius, akan tetapi hal ini tetap akan membawa dampak bagi pilihan politik hukum dan kelangsungan peradaban (hukum) masyarakat Indonesia dalam memahami nilai-nilai ke-Indonesiaan-an yang termuat dalam ideologi Pancasila sebgai grundnorm yang merupakan abstraksi dari (nilai) The Original Paradicmatic Values of Indonesia Culture and Society . B. Perubahan dan Pergeseran Nilai Ketuhanan Tujuh puluh delapan hari menjelang kemerdekaan, tepatnya tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno dalam pidatonya meletakkan dasar negara yang ia beri nama “Pancasila”. Ide dan gagasan tentang Pancasila itu bukan serta merta lahir begitu saja tapi mengalami proses yang panjang. Yang oleh Judi Latif, 161 disebutnya sebagai warisan jenius nusatara. Pancasila adalah abstraksi the reality of the original paradicmatic Velues of Indonesian Culture and society yang digali dari bumi Indonesia sendiri, sebagaimana diungkapkan Bung Karno dalam berbagai pidatonya.Satu malam di malam tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno berdo’a, karena keesokan harinya ia akan menyampaikan pidato 160 Kartadjoemena berpandangan bahwa Indonesia punya kepentingan dalam Uruguay Round, dalam perspektif Indonesia, menurutnya Uruguay Round merupakan pengalaman baru dalam menangani masalah perdagangan internasional secara integratif. Namun, dikemukakannya bahwa dilihat dari segi timing, waktunya bertepatan dengan tahapan baru dalam kebijakan ekonomi dalam negeri yang mengarah kepada upaya peningkatan eksport non migas dan peningkatan efisiensi melalui deregulasi, debirokratisasi dan penyesuaian secara struktural. Untuk pertama kalinya aturan permainan dalam GATT/WTO 1994 menjadi faktor yang penting dan langsung berkaitan dengan kepentingan nasional Indonesia di bidang perdangan. Lihat lebih lanjut H.S. Kartadjoemena, GATT WTO dan Hasil Uruguay Round, UI Press, Jakarta, 1997, hal. 1415. 161 Yudi Yudi Latif, Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila, Gramedia, Jakarta, 2011, hal. 2. 253 di hadapan sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai, untuk menjawab sebuah pertanyaan tentang Dasar Negara Indonesia Merdeka. Dalam sebuah pidatonya, demikian dikutif oleh Judi Latif, Bung Karno mengatakan : Di tengah malam yang esok harinya adalah giliran saya akan mengucapkan pidato saya keluar dari rumah di Jalan Pegangsaan Timur No.56. Saya keluar di malam yang sunyi itu dan saya menengadahkan wajah saya ke langit. Saya melihat bintang gemerlapan, ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu dan di sinilah saya merasa betapa kecilnya manusia. Di situlah aku merasa dha’ifnya aku ini. Di situlah aku merasa pertanggung jawaban yang amat berat dan besar yang diletakkan di atas pundak saya............. Ya Tuhan, ya Allah, ya Rabbi besok pagi aku harus memberi jawaban atas pertanyaan yang maha penting ini..............berilah aku petunjuk. Setelah aku mengucapkan do’a aku mendapat petunjuk, mendapat ilham. Ilham yang berkata “galilah apa yang hendak kau jawab itu dari bumi Indonesia sendiri.” Maka malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku menggali di dalam hayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari pengalaman itu dapat dipakai sebagai dasar daripada Negara Indonesia Merdeka yang akan datang. 162 Sebagai penggali, penggagas Pancasila, Bung Karno sadar betul akan arti pentingnya meletakkan Dasar Negara di atas kepribadian bangsa sendiri. Dasar yang digali dari bumi Indonesia sendiri setelah mencermati perjalanan bangsanya. Memang pada awalnya ada banyak tawaran ideologi yang diajukan dalam sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai. Ada yang mengusulkan negara ini dibangun di atas landasan ideologi Sosialis. Ada juga suara-suara nyang menghendaki ideologi marxis. Ada juga yang mengusulkan di atas ideologi Islam negara ini didirikan. Bung Karno dalam pidatonya dengan mengambil contoh di beberapa negara, seperti Arab Saudi didirikan oleh Ibnu Saud di atas ideologi Islam, Lenin mendirikan negara soviet di atas weltanshauung Marxistische, Hitler mendirikan Jerman di atas weltanschauung National Sozialistische, Negara Dai Nippon didirikan di atas weltanschauung Tenoo Koodoo Seishin. Sun Yat Sen mendirikan negara Tiongkok di atas San Min Chu I (Mintsu, Minchuan, Min Seng dan nasionalism). Itulah “isi” negara-negara merdeka yang didirikan oleh the founding fathernya masing-masing. Itulah yang oleh Bung Karno disebutnya sebagai sebuah perbedaan “isi” di masing-masing negara berdasarkan derajat dan pengalaman sejarah negaranya. 162 Ibid, hal. 13. 254 Pancasila dalam banyak literatur 163 dikatakan sebagai hasil perasan dari sari pati kehidupan sosio-kultural bangsa Indonesia. Sari pati peradaban, saripati budaya, sari pati yang dirumuskan oleh pemikir dan the founding fathers negara ini yang secara methodologis merupakan hasil abstraksi dari nilai-nilai original paradigmatik sosial dan kultural rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila yang telah disepakati oleh para the founding fathers bangsa Indonesia, secara objektif dikagumi oleh seorang ahli tentang Indonesia, dari Cornell University USA, George Mc Turner Kahin, sebagaimana dikatakan Yudi Latif ; Dalam bukunya Nationalsm and Revolution, Kahin menyebut bahwa rumusan ideologi Pancasila diungkapkannya “Pancasila is the best exposition of history I have ever seen”. Nilai filosofis yang terkandung dalam Pancasila juga diapresiasi oleh filsuf Inggris, Bertrand Russell yang dikatakannya bahwa Pancasila merupakan suatu sintesis kreatif antara Declaration of American Independence (yang merepresentasikan ideologi demokrasi kapitalis), dengan Manifesto Komunis (yang merepresentasikan ideologi komunis). Pandangan terhadap filsafat Pancasila juga dikemukakan oleh Routges yang menyatakan bahwa “Dari semua negara-negara di Asia Tenggara, Indonesialah yang dalam konstitusinya, pertama-tama dan paling tegas melakukan latar belakang psikologis yang sesungguhnya dari semua revolusi melawan penjajah. Dalam filsafat negaranya Pancasila, dilukiskan alasan-alasan secara lebih mendalam daripada revolusi-revolusi itu. Berdasarkan perspektif lain Koentowijoyo menekankan pentingnya radikalisasi Pancasila dalam negara Indonesia yaitu bagaimana meletakkan Pancasila secara radikal dan efektif sebagai pedoman bagi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. 164 Nilai-nilai paradigmatik sosio kultural yang terabstraksi dalam Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara itu telah pernah diturunkan secara formal dalam bentuk penggalan asasasas yang terkandung dalam lima sila itu yang dimuat dalam TAP MPR NO/II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. 163 Lihat lebih lanjut Yudi Yudi Latif, Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila, Gramedia, Jakarta, 2011 dan H. Kaelan, Negara Kebangsaan Pancasila Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya, Paradigma, Yogyakarta, 2013. 164 H. Kaelan, Ibid, hal. 4-5. 255 Asas-asas itu dapat dijadikan dasar bagi penyusunan tertib hukum, jika Pancasila dimaknai sebagai kontatasi filosofis. Sebagai falsafah negara, sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian Pancasila akan dapat mewarnai tata hukum yang berlaku di Indonesia. Akan terlihat warna Pancasila dalam norma hukum konkrit yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penempatan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila pada sila pertama bukanlah secara kebetulan akan tetapi mempunyai nilai dan makna politis yang didalamnya tersirat bahwa sila pertama ini akan menjiwai seluruh sila-sila yang lainnya. Oleh karena itu jika nilainilai dalam sila pertama ini dapat diadopsi dengan baik dalam penyusunan materi undang-undang maka secara substansi untuk satu pekerjaan berat yakni meletakkan dasar hukum dalam negeri ini telah selesai. Artinya sila pertama menjadi kunci untuk tegaknya nilai-nilai sila yang lain. Tinggal kemudian bagaimana hukum itu dijalankan di tengah-tengah masyarakat. Sebagai suatu bangsa yang telah berabad-abad lamanya meyakini tentang adanya Sang Maha Kuasa Pencipta Alam Semesta, maka pilihan keyakinan itu telah menjadi dasar pembentukan karakter religius masyarakat Indonesia. Ada anggapan saat ini nilai-nilai Ketuhanan itu hanya tepat atau cocok untuk dipergunakan dalam hubungannya dengan menjalankan aktivitas ibadah rutin. Padahal nilai Ketuhanan itu adalah nilai yang dianut oleh sebahagian besar masyarakat dan bangsa-bangsa yang ada di dunia. Nilai Ketuhanan di Indonesia dipandang sebagai warisan leluhur yang bersumber dari agama-agama besar yang pernah ada di bumi Indonesia. Sebagai suatu nilai, nilai Ketuhanan itu tidak hanya merupakan doktrin yang bersifat statis akan tetapi bertolak dari nilai itu dapat dikembangkan norma-norma hukum konkrit sesuai tuntutan zaman. Dalam nilai Ketuhanan itu tersembunyi paling tidak ada 4 (empat) asas meliputi : 1. Asas Ketuhanan 2. Asas saling menghormati dan asas kerukunan 3. Asas toleransi 4. Asas kebebasan memilih 165 Keempat asas ini satu dan yang lainnya saling berkait. Namun dapat dijadikan sebagai dasar dalam pembentukan norma hukum. Wujudnya 165 Mahadi, Filsafat Hukum, Op.Cit, hal. 156. 256 adalah nilai Ketuhanan itu dipakai sebagai dasar guna merumuskan ketentuan-ketentuan normatif yang akan dituangkan dalam produk legislatif. Dalam Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, serapan asas Ketuhanan tersebut dapat dilihat pada Pasal 17 yakni tentang larangan pengumuman setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang agama dan kesusilaan. Akan tetapi asas tersebut tidak terlihat diterapkan ketika merumuskan tentang pengertian atau batasan tentang hak cipta. Dalam Undang-undang Hak Cipta Nasional rumusan tentang hak cipta sejak Auteurswet 1912 Stb. No. 600 sampai dengan sekarang hak cipta didefenisikan sebagai hak khusus atau hak eksklusif bagi pencipta. Istilah hak eksklusif yang diadopsi dari istilah exclusive rights atau hak khusus yang digunakan oleh undang-undang hak cipta sebelumnya. Ketentuan ini sebenarnya ditransplantasi dari ketentuan Pasal 1 Auteurswet Stb. 1912 No. 600 dengan menggunakan istilah hak tunggal. Jika pembuat undang-undang hak cipta nasional mengacu pada nilai filosofis Pancasila yakni nilai Ketuhanan rumusan Pasal 1 hak cipta itu akan berbunyi lain dari yang ada sekarang ini. Hak cipta tidak lagi disebut sebagai hak eksklusif bagi pencipta tetapi adalah hak pencipta yang lahir atas berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Dengan rumusan yang demikian, para pencipta akan mengagungkan dan bersyukur kepada Tuhannya yang telah memberikannya talenta, ilmu pengetahuan, kesehatan dan keluangan waktu untuk dapat menghasilkan karya cipta. Sekilas terlihat bahwa redaksi pasal yang secara inplisit memuat nilai Ketuhanan seolah-olah terlihat tidak begitu berguna atau bermanfaat secara redaksional, akan tetapi menempatkan nilai Ketuhanan secara inplisit akan menggambarkan bahwa manusia sesungguhnya tidak mempunyai nilai ciptaan apapun dihadapan Tuhannya jika dibandingkan dengan ciptaan Tuhannya. Pemaknaan yang demikian untuk selanjutnya akan berpengaruh pula kepada pasal-pasal lain yang misalnya terhadap ciptaan yang tidak diketahui siapa penciptanya tidak lagi harus dipegang oleh negara tetapi diberikan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkannya, karena ciptaan yang demikian itu lahir atas hamba Tuhan yang tidak diketahui. Ketentuan semacam itu adalah salah satu contoh kecil saja dalam mengadopsi nilai Ketuhanan (sebagai landasan filosofis pembuatan undang-undang) ke dalam undang-undang hak cipta nasional. Ketentuan undangundang hak cipta saat ini dan juga pada masa lalu tanpa disadari lepas dari kebijakan politik pembangunan hukum nasional karena tidak sepenuhnya menekankan bahwa pentingnya pemahaman terhadap 257 landasan filosofis Pancasila yang memuat sejumlah asas yang dapat dijadikan dasar bagi pembentukan norma hukum. Demikian juga dengan nilai Ketuhanan akan menempatkan manusia pada wujud kepatuhannya kepada Sang Pencipta. Wujud kepatuhan itu mestinya juga dapat dilihat dalam perjalanan sejarah pembentukan undang-undang hak cipta nasional. Peradaban Barat modern yang memunculkan nilai sekularis tidak terlepas dari perjalanan sejarah menjelang pertengahan abad ke19. Peran agama yang dipisahkan dari pemaduan kehidupan politik, ekonomi dan sosial pada tahun-tahun itu telah memudar secara signifikan. Adalah revolusi Perancis yang memicu kebangkitan industrialisasi di Eropa Barat dan menggerakkan migrasi ke daerah perkotaan sejalan dengan itu terjadi pertumbuhan ekonomi yang luar biasa yang memposisikan nilai material semakin menguat di atas nilai spiritual dan melemahnya kepercayaan atas nilai-nilai keagamaan yang pada gilirannya terhentinya pengaruh agama terhadap kehidupan politik. Inilah yang oleh Robert Owen memunculkan kata “sekulerism” di pertengahan abad ke-19 untuk menyebutkan serangkaian kepercayaan yang didasarkan pada pertimbangan manusiawi dan materialis semata-mata dan melepaskan pertimbangan teologi. 166 Pola pikir sekuler itu adalah merupakan hasil dari pergeseran pandangan filosofi yakni yang semula didasarkan pada pandangan teologi (Ketuhanan) bergeser kepada pandangan penalaran ilmiah dan ilmu pengetahuan yang liberal yang didasarkan kepada penalaran manusia yang membuahkan nilai-nilai materialisme. Dalam perspektif Ketuhanan keberadaan manusia maupun keberadaan ilmu pengetahuan adalah bersumber dari kekuatan Tuhan. 167 Data tahun 2002, memperlihatkan bahwa sebahagian besar bangsa-bangsa di dunia telah mengarah kepada kehidupan sekuler seperti yang tergambar pada matrik di bawah ini : 166 Eamonn Kelly, Agenda Dunia Powerful Times Abad 21, Bangkit Menghadapi Tantangan Dunia Yang Penuh Ketidakpastian, Index, Jakarta, 2010, hal. 56. 167 Dalam pandangan teologi Islam, bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan dan ilmu pengetahuan hanya sedikit sekali yang diberikan oleh Tuhan untuk memahami fenomena alam, sebagai wujud dari ciptaan Tuhan. Lebih lanjut lihat Fazlur Rahman, Tema Pokok Al-Qur'an, Penerbit Pustaka, Bandung, 1983. 258 Matrik 29 Pentingnya Agama Dalam Kehidupan Negara Bagian Amerika Utara Eropa Barat Eropa Timur Area Konflik Amerika Latin Asia Afrika Sumber : Negara AS Canada Inggris Italia Jerman Perancis Polandia Ukrania Slowakia Rusia Bulgaria Czech Pakistan Turki Uzbek Guatemala Brazil Honduras Peru Bolivia Venezuela Mexico Argentina Indonesia India Filipina Bangladesh Korea Vietnam Japan Senegal Nigeria Pantai Iv Mali Afrika Selatan Kenya Uganda Ghona Tanzania Angola Persentase kepercayaan rakyatnya terhadap Agama 59% 30% 33% 27% 21% 11% 36% 35% 29% 14% 13% 11% 91% 65% 35% 80% 77% 72% 69% 66% 61% 57% 39% 95% 92% 88% 88% 25% 24% 12% 97% 92% 91% 90% 87% 85% 85% 84% 83% 80% Eamonn Kelly, Agenda Dunia Powerful Times Abad 21, Bangkit Menghadapi Tantangan Dunia Yang Penuh Ketidakpastian, Index, Jakarta, 2010 259 Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dilihat bahwa Perancis, Czech, Jepang, Bulgaria kemudian menyusul Rusia adalah negara-negara yang memiliki kecenderungan ke arah sekularisme dalam pandangannya terhadap dunia yang berpusat pada pemikiran manusia. Jerman, Inggris dan Italia juga bergerak ke arah pemikiran sekularisme. Di Asia Korea, dan Vietnam juga memperlihatkan kecenderungan ke arah sana. Kesimpulannya, negara-negara ekonomi maju baik di Eropa maupun Asia semakin jauh dari kedekatannya terhadap alam pikiran Ketuhanan dan bergerak menuju kehidupan sekuler. Sekularisme, mempercepat langkah-langkah pragmatism dan cita-cita kehidupan yang bersumber pada optimisme ditempatkan pada nilai tertinggi yakni pengetahuan dan wawasan serta ide yang dapat menyelesaikan dan mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh umat manusia tanpa merujuk pada nilai-nilai Ketuhanan. Dalam agama-agama besar yang dianut oleh masyarakat di dunia, nilai ketuhanan yang juga diikuti oleh nilai keadilan itu menjadi kata kunci. Dalam Islam, kata “adil” adalah kata-kata kedua yang terbanyak disebut dalam Al-Quran setelah kata “Tuhan”. 168 Nilai Ketuhanan yang diadopsi oleh tidak berpangkal pada mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi bertumpu pada pemerataan pendapatan atau pendistribusian kekayaan negara secara adil dan merata. Tidak perlulah pertumbuhan itu sampai 5% atau 7% yang diperlukan justru pemerataan. Jika seandainya pertumbuhan itu 1% saja tapi didistribusikan secara merata, situasi keamanan dalam negeri mungkin lebih dapat dikendalikan ketimbang pertumbuhan 7% akan tetapi dikuasai oleh sekelompok orang tertentu, seperti yang terjadi selama kurun waktu Pemerintahan Orde Baru dan belum berakhir sampai pada pemerintahan pasca reformasi. 169 168 Lihat lebih lanjut Fazlul Rahman, Tema Pokok Al-Qur'an, Penerbit Pustaka, Bandung, 1983. 169 Karena keruntuhan Orde Baru tidak seperti keruntuhan orde pemerintahan Soekarno. Pada masa pemerintahan Soekarno, keruntuhannya diikuti dengan keruntuhan kroni-kroni bisnisnya seperti Jusuf Muda Dalam yang turut tenggelam dalam usaha bisnisnya bersamaan dengan keruntuhan pemerintahan Soekarno. Berbeda dengan Soekarno, keruntuhan orde pemerintahan Soeharto tidak menyebabkan runtuhnya kronikroni bisnis yang berjaya pada zaman Soeharto. Liem Sio Liong misalnya, membangun usaha bisnisnya dan dikendalikannya dari Singapura. Partai yang berkuasa pada zaman Soeharto pun yang relatif dipimpin oleh para pengusaha dan konglomerat pada zaman pemerintahan Soeharto sampai hari ini masih eksis. Karena itu gagasan kapitalis yang tumbuh pesat pada zaman pemerintahan Orde Baru tampaknya masih akan berlanjut pada orde pemerintahan reformasi. Cerita-cerita ini sudah disinyalir dengan baik oleh Richard Robinson, sejak masa colonial namun tumbuh pesat pada masa Pemerintahan Orde Baru. 260 Tumbuhnya faham kapitalis adalah sebagai resultan dari berbagai-bagai pandangan pragmatis, politik praktis, pengabaian terhadap nilai-nilai ketuhanan, nilai keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan yang berpangkal pada faham sekularisme. Kebangkitan sekularisme terkait dari pandangan terhadap dunia yang berpusat pada rasio. Memang, untuk memahami unsur-unsur yang ada pada nilai Ketuhanan mengacu pada argumentasi-argumentasi yang dalam yang diurai berdasarkan pendekatan ilmiah. Hasil dari penalaran manusia, jika tidak dikendalikan dengan pandangan-pandangan Ketuhanan akan membuahkan suatu impian yang dahsyat, seolah-olah impian itu adalah sesuatu yang sangat ideal. Padahal semua ini demikian tulis Eamonn Kelly adalah bersumber dari pandangan pencerahan yang relatif baru yakni pada awal abad ke-19. Sistem demokrasi, kemerdekaan, kebebasan individu semua itu tumbuh dari modernitas sekuler. 170 Indonesia sekalipun data tersebut memperlihatkan warga negaranya masih hidup dalam suasana religius dan mengakui adanya Tuhan yakni 95%, akan tetapi dalam praktek kesehariannya sudah mulai bergerak ke arah sekuler. Kecenderungan ini ditandai dari praktek-praktek ketatanegaraan dan praktek-praktek pemerintahan serta praktek-praktek bisnis, pendidikan, politik dan hukum yang kesemuanya memperlihatkan adanya kecenderungan ke arah sekularisme. Praktek transplantasi hukum asing ke dalam hukum nasional yang bersumber dari peradaban Barat di Indonesia adalah satu contoh konkrit praktek penyerapan nilai-nilai sekularisme. Dalam kasus transplantasi undang-undang hak cipta nasional misalnya, praktek penyerapan nilai-nilai sekularisme itu sudah terlihat sejak diberlakukannya Auteurswet Stb. 1912 No. 600 di wilayah jajahan Kolonial Belanda dan itu diteruskan sampai pada zaman kemerdekaan dan berlanjut terus pada beberapa periode kepemimpinan negara berikutnya yang sebenarnya telah terbuka kesempatan luas untuk menyusun undang-undang hak ciptanya sendiri dengan nilai-nilai ke-Indonesia-an” . Sejarah pembentukan undang-undang hak cipta nasional (Indonesia) tidaklah berdiri sendiri, terjadi dengan serta merta atau mengikuti arus gerak secara linier, tapi ia terjadi dengan melibatkan banyak peristiwa yang melatar belakanginya. Peristiwa sejarah yang Lihat lebih lanjut Richard Robinson Indonesia The Rise of Capital, Equinox Publishing, Jakarta, 2008, hal. 3 dan 105-176. 170 Eamon Kelly, Op.Cit, hal. 58. 261 penuh dengan liku-liku (non linier) yang diwarnai oleh berbagai keinginan pemerintah kolonial ketika itu di satu sisi dan di sisi lain perjuangan untuk menegakkan hukum adat terus bergema yang dimotori oleh ilmuwan bangsa Belanda sendiri bersama-sama dengan pengikutnya. 171 Tidak ada dalil yang kuat yang dapat mengantarkan pandangan ilmiah akademik yang menyimpulkan bahwa masyarakat Indonesia (dalam sejarahnya) adalah masyarakat dengan steriotip negatif terhadap kepatuhannya pada ajaran agama. Bait-bait syair berikut ini menggambarkan jati diri bangsa Indonesia sebagai the original paradigmatic value of Indonesian culture and society. 172 Apa tanda bangsa sejati Bersama agama dia mati Bait di atas meperlihatkan karakter bangsa Indonesia yang sejati. Ciri-ciri bangsa Indonesia yang bertuhan, bangsa yang mengakui keberadaan Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari dan baru berakhir setelah ajal atau kematian menjeputnya. Apa tanda bangsa religi Tuhan dipuji tiada henti Nilai melekat di dalam hati Nilai-nilai religius yang setiap hari menjadi pedoman untuk bersikap telah dilekatkan di dalam hati sanubari masyarakatnya dan itu menjadi karakter bangsa yang religius. Apa tanda bangsa bertuah Memeluk agama tiada menyalah Sebarang laku menurut sunnah Hidup mati dengan aqidah Tuhan telah mengucurkan rahmat dan karuniaNya terhadap bangsa ini. Tidak semua bangsa dapat kucuran Rahmat yang demikian. Di berbagai belahan dunia, masyarakat hidup tanpa keyakinan adanya Tuhan, tanpa ada panduan agama. Negara-negara komunis trelah lama meniadakan faham keagamaan itu dalam jiwa dan hati sanubari rakyatnya. Oleh karena itu menurut frase bahasa Melayu, negeri ini adalah negeri yang bertuah, negeri yang mendapat “tuah” dalam arti mendapat berkah mendapat petunjuk dari Tuhan. Karena itu masyarakatnya sejak zaman lampau tak pernah ingkar dari ajaran agamanya. Selalu tunduk dan patuh terhadap ajaran agama, yang menjadi ciri-ciri atau karakter bangsa Indonesia. 171 Lebih lanjut lihat Soetnadyo Wignyosoebroto, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 1994. 172 Tenas Effendy, Tunjuk Ajar Melayu (Butir-butir Budaya Melayu Riau, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta, 2004, hal. 67. 262 Apa tanda bangsa pilihan Hidup mati dalam iman Taat setia menyembah Tuhan Dalam agama tiada menyeman. 173 Karakter bangsa yang demikian bukan karakter bangsa yang terwujud dengan sendirinya, tapi itu adalah karakter bangsa yang “dipilih” oleh Tuhan. Suatu bangsa tidak akan mendapat petunjuk jika Tuhan mau menyesatkan, dan bangsa yang telah mendapat petunjuk dari Tuhan, tidak akan ada yang dapat menyesatkannya. Oleh karena itu bangsa ini adalah bangsa yang terpilih sebagai bangsa yang mendapat petunjuk dari Tuhan. Masyarakatnya senatiasa beriman dan patuh kepada Tuhannya, itulah karakter bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Terdapat karakter bangsa yang sejak awal telah melekat nilainilai Ketuhanan dalam jiwa dan sanubari rakyatnya. Ketaatan atau kepatuhan terhadap ajaran dan keyakinan agama dipegang teguh. Ajaran dan nilai-nilai agama dan keyakinan dijadikan pedoman untuk berprilaku hingga kematian menjeputnya. Nilai-nilai inilah kemudian diabstraksikan sebagai “Nilai Ketuhanan”, yang ditempatkan dalam Sila Pertama. C. Perubahan dan Pergeseran Nilai Kemanusiaan Dalam sejarah perjalanan undang-undang hak cipta, sejak semula telah diawali oleh dominasi politik hukum Kolonial. Pemberlakuan Auteurswet 1912 Stb. No. 600 adalah wujud dari keinginan pemerintah Kolonial Belanda untuk memberlakukan undangundang yang berasal dari negerinya untuk diberlakukan di dalam wilayah negeri jajahannya. Meskipun politik hukum Pemerintahan Hindia Belanda ketika itu masih memberikan klasifikasi pada tiap-tiap golongan penduduk sebagaimana telah dikukuhkan dalam Pasal 131 IS dan Pasal 163 IS 174 semua langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda baik itu mengenai tugas-tugas yang bersangkut paut dengan upaya kodifikasi maupun tugas-tugas yang 173 Menyeman dalam bahasa Melayu bermakna terkontaminasi. Pasal 163 IS membagi golongan penduduk Indonesia ke dalam tiga golongan yaitu golongan Eropa, golongan Bumi Putera dan golongan Timur Asing. Bagi golongan Eropa, menurut Pasal 131 IS berlaku hukum Eropa dan bagi golongan Bumi Putera berlaku hukum adat sedangkan bagi golongan Timur Asing berlaku hukum adat dan bila keperluan sosial mereka menghendakinya membuat ordonansi dapat menentukan bagi mereka untuk diberlakukan hukum Eropa atau hukum Eropa sesudah diubah atau hukum baru yang merupakan sintesa dari hukum Barat dengan hukum Eropa. Lebih lanjut lihat E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Ichtiar Baru, Jakarta, 1983, hal. 167-168. 174 263 berhubungan dengan pemberlakuan hukum yang berasal dari negeri asal. Semua itu diprakarsai secara sadar dan ditaja oleh eksponeneksponen bewuste rechtspolitiek yang tujuannya adalah untuk mengukuhkan tegaknya supremasi hukum di tanah jajahan. 175 Supremasi hukum di tanah jajahan akhirnya diwarnai juga dengan pemberlakuan undang-undang di luar kitab undang-undang yang telah terkodifikasi antara lain adalah Undang-undang tentang hak cipta seperti disebutkan di atas. Pemaksaan pemberlakuan undangundang hak cipta itu seringkali menjadikan masyarakat tempat hukum itu diberlakukan menjadi masyarakat yang mendua dan cenderung melahirkan sikap ambivalen. Seringkali kehidupan bersama itu justru diatur oleh kaidah atau norma hukum yang hanya disepakati oleh sekelompok orang saja atau oleh sekelompok penguasa saja atau oleh sekelompok partai politik saja, kemudian dipaksakan berlakunya untuk semua orang. Meskipun norma semacam itu diakui sebagai hukum akan tetapi jika hukum semacam itu ditegakkan tidaklah dapat dikatakan itu telah memenuhi unsur-unsur negara hukum. 176 Kekuasaan pada hakekatnya dalam konsep negara hukum, adalah sebuah amanah yang diberikan oleh hukum. Kekuasaan yang 175 Lebih lajut baca : Soetandiyo Wignjosoebroto, Loc.Cit, hal. 47. Meskipun pada tahap-tahap awal usaha mereka untuk melakukan kodifikasi perdata dan hukum dagang telah selesai, akan tetapi ada permasalahan lain yang belum selesai yakni ikhwal unifikasi hukum yang meliputi tak hanya yang bersifat substantif tapi juga yang formal prosedural berikut tata peradilannya dan itu menimbulkan polemik. Polemik-polemik itu berkisar apakah kodifikasi hukum yang disiapkan untuk orang-orang Eropa juga diperlakukan untuk kepentingan orang-orang pribumi. Jika ya, apakah orang-orang tersebut harus tunduk pada peradilan yang diperuntukkan bagi orang Eropa ? Polemik inilah yang muncul dikemudian hari, namun dapat dirasakan bahwa pada akhirnya penduduk pribumi ketika itu mulai secara perlahan-lahan menundukkan diri pada hukum Eropa. Buahnya adalah hari ini dimana tradisi peradilan telah mengantarkan masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan model peadilan yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada zaman dahulu. 176 Hukum haruslah dibedakan dengan undang-undang, karena itu konsep negara hukum tidak sama dengan konsep negara undang-undang. Bahwa undang-undang adalah sebahagian dari hukum dapat diterima, akan tetapi tidak semua hukum itu dalam bentuk undang-undang. Ada hukum tertulis dan ada hukum yang tidak tertulis. Ada hukum yang bersumber dari undang-undang, ada pula hukum yang bersumbe dari adatistiadat dan agama. Karena itu konsep mengadili menurut hukum juga berbeda dengan konsep mengadili menurut undang-undang. Di negara yang plural seperti Indonesia, pemaknaan negara hukum akan membawa suatu konsekuensi logis bahwa hukum yang diberlakukan tidaklah semata-mata berupa hukum produk lembaga legislatif, akan tetapi hukum-hukum yang lahir di tengah-tengah masyarakat seperti hukum adat dan kebiasaan serta hukum agama tetap akan memegang peranan penting dalam pemaknaan negara hukum. 264 tidak diberikan oleh hukum akan dapat berubah menjadi otoriter, 177 bahkan cenderung tirani. 177 Lahirnya konsep negara hukum diawali dari perjalanan yang cukup panjangdiawali dari gagasan demokrasi pada jaman Yunani yang berkembang pada abad ke-6 sampai dengan abad ke-3 SM gagasan demokrasi ini kemudian lenyap di Barat sejak Romawi dikalahkan oleh Eropa Barat yang kemudian dikuasai berdasarkan agama Nasrani (Katolik). Di Barat pada waktu itu dikembangkan pemikiran sosial dan spiritual harus tunduk pada Paus (gereja) dan pejabat agama sedangkan kehidupan politik harus tunduk pada raja. Situasi ini kemudian menimbulkan kegelapan di dunia Barat dan kemudian dipecahkan dengan munculnya zaman Renaissance (1350-1600 M). Kemunculan ini dipicu oleh peristiwa Perang Salib yang berlangsung tidak kurang dari 2 abad. (1096-1291). Perang salib ini telah memunculkan komunikasi antara Barat dengan Dunia Islam. Dan ini menimbulkan gagasan di kalangan dunia barat perlunya kebebasan, dan penghormatan terhadap hak-hak rakyat. Gagasan ini kemudian terus berkembang dan memasuki abad yang menuntut pendobrakan pemikiran yang selama ini dibatasi oleh Gereja. Ini terjadi sampai dengan Tahun 1850. Giliran berikutnya adalah timbul gagasan di bidang politik bahwa manusia mempunyai hak yang tidak boleh diselewengkan oleh pemerintah, dan absolutisme dalam pemerintahan harus didobrak. Pemikiran semacam ini muncul yang kemudian mendasari dari berkembangnya teori kontrak sosial. Teori tersebut kemudian secara cepat tumbuh dan berkembang yang akhirnya muncullah ideide, gagasan bahwa pemerintahan harus diselenggarakan secara konstitusional. Inilah perjalanan kelahiran konsep negara hukum. Friedrich Julius Stahl dari kalangan Eropa Kontinental, mengemukakan adanya empat unsur negara hukum (rechtsstaat) yaitu : pertama, hak asasi manusia ; kedua pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin HAM (termasuk adanya kekuasaan kehakiman seperti dikenal di dalam Trias Politika); ketiga, pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan dan keempat peradilan administrasi dalam perselsihan. Sementara itu, AV. Dicey yang merupakan ahli dari kalangan Anglo Saxon, menyebutkan unsure-unsur negara hukum (yang disebutnya the rule of law) sebanyak tiga macam. Pertama, supremasi hukum, tidak ada kesewenangwenangan kekuasaan sehingga orang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum, kedua, adanya kesamaan di depan hukum dan ketiga terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang maupun oleh putusan pengadilan. Pencirian atau penyebutan unsureunsur negara hukum tersebut menunjukkan bahwa adanya lembaga peradilan merupakan salah satu hal yang mutlak. Dan karena fungsinya untuk memberikan keadilan atas perselisihan berbagai pihak, maka keberadaan lembaga peradilan itu sudah tentu haruslah bebas dari campur tangan kekuasan yang ada di luar dirinya. Lebih lanjut lihat, Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 89-91. Lebih lanjut lihat David Jenkins, Soeharto & Barisan Jenderal Orba Rezim Militer Indonesia 1975-1983, Komunitas Bambu, Jakarta, 2010. Mahpudi, dkk, Pak Harto The Untold Stories, Gramedia, Jakarta, 2013. Julie Soulthwood-Patrick Flanagan, Teror Orde Baru Penyelewengan Hukum & Propaganda 1965-1981, Komunitas Bambu, Jakarta, 2012. Lihat lebih lanjut Widjanarko Puspoyo, Dari Soekarno Hingga Yudhoyono, Pemilu Indonesia 1955-2009, Era Adicitra Intermedia, Solo, 2012. Bandingkan juga dengan Hanta Yuda AR, Presidensialisme Setengah Hati Dari Dilema ke Kompromi, Gramedia, Jakarta, 2010. Lihat juga Riwanto Tirtosudarmo, Mencari Indonesia Demografi-Politik Pasca-Soeharto, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007 dan bandingkan juga dengan AM Waskito, Republik Bohong Hikayat Bangsa Yang Senang Ditipu, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2011. Lebih lanjut lihat David Runciman, Politik Muka Dua Topeng Kekuasaan dari Hobbes hingga Orwell, Pustaka Pelajar, 265 Pada zaman pemerintahan Soeharto dan awal pemerintahan pasca reformasi, yakni saat-saat dilahirkannya Undang-undang Hak Cipta Nasional adalah sisi gelap dari praktek negara hukum Indonesia. Pada zaman Pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru dan awal-awal pemerintahan orde reformasi praktek penegakan hukum berjalan dan mengalir sesuai keinginan pemerintah. Bahkan praktek penyalahgunaan kekuasaan dan praktek pelanggaran hukum oleh badan-badan penyelenggara negara pun tidak menjadi sesuatu yang dianggap salah jika pemerintah menghendaki.178 Ketika semua anggota legislatif yang “berwajah banyak” itupun duduk untuk merumuskan UU Hak Cipta Nasional dan satu persatu memberikan usulan lalu secara kelembagaan membungkus keputusannya untuk dan atas nama demokrasi. 179 Padahal di balik keputusan itu ada kekuasaan dan “titipan” yang “mendompleng”. Adalah kepentingan Amerika dengan berbagai tekanan politik dan Yogyakarta, 2012. Lebih lanjut lihat Fahri Hamzah, Kemana Ujung Century ? Penelusuran dan Catatan Mantan Anggota Pansus Hak Angket Bank Century DPR-RI, Yayasan Faham Indonesia, Jakarta, 2011. Lihat juga Rafat Ali Rizvi dan Hesham Al Warraq, Skandal Bank Century Lolosnya Pemegang Saham Pengendali, Pusat Pengkajian Hukum Acara dan Sistem Peradilan, FH-UI, Jakarta, 2012. 178 Kasus penembakan misterius dan kasus kematian Munir adalah contohcontoh yang dapat menguatkan anggapan bahwa negeri ini dalam perjalanannya telah melakukan tindakan yang jauh dari ide dan gagasan negara hukum. Ini adalah bahagianbahagian kasat mata yang dapat ditangkap dengan indra. Bagaimanapun juga terlalu banyak catatan dan sisi gelap dari pelanggaran-pelanggaran negara terhadap hak-hak masyarakat bahkan hak asasi manusia yang tidak terungkap. Kasus Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh yang membuahkan jerit tangis dan air mata anak-anak, wanita dan sebahagian rakyat di Aceh adalah satu contoh yang menggambarkan betapa konsep negara hukum hanya tinggal di atas kertas. Meskipun akhirnya perundingan Helsiky membuahkan hasil yang memberikan otonomi khusus kepada rakyat dan masyarakat Aceh. Persoalan-persoalan lain menyangkut pelanggaran-pelanggaran masyarakat adat seperti perampasan tanah adat, pengambil alihan hutan rakyat untuk dan atas nama konservasi hutan, nasionalisasi perkebunan asing yang menegasikan hak-hak masyarakat puak Melayu (Deli, Langkat, Asahan, Serdang, Batubara, Kota Pinang, Bilah, Panai dan Kuwaluh) adalah contoh-contoh konkrit tentang perjalanan bangsa ini yang mengabaikan konsep negara hukm yang telah dipilihnya sendiri. 179 Demokrasi adalah salah satu ciri dari konsep negara hukum. Untuk dan atas nama negara hukum, para anggota legislatif duduk dan berkumpul untuk merumuskan kontrak sosial dalam pembuatan undang-undang hak cipta nasional. Undang-undang hak cipta nasional adalah bahagian dari hukum nasional yang berakar pada dasar filosofis Pancasila. Pancasila yang disepakati sebagai paradigma politik hukum tidak serta merta kemudian dijadikan sebagai landasan dasar penyusunan undangundang hak cipta nasional. Hasilnya adalah undang-undang hak cipta nasional jauh dari kesan landasan ideologi itu, yang memperlihatkan terjadinya pergeseran paradigma. 266 tekanan ekonomi yang kemudian terakomodir.180 Jadilah undangundang hak cipta nasional dengan menggerus sebagian dari nilai-nilai Pancasila. Produk legislatif yang berbentuk undang-undang isinya bisa melulu nuansa kekuasaan. Isinya bisa menjastifikasi kekuasaan dan sebaliknya mengkriminalisasi masyarakat. Itulah sebabnya negeri ini dengan mudah terjerembab dalam jerat kekuasaan. Ketika seseorang ingin mendapatkan sesuatu yang tadinya perbuatan itu dilarang secara moral dan etika, akan tetapi menjadi boleh ketika dibuatkan terlebih dahulu undang-undangnya. 181 Proses kelahiran undang-undang hak cipta nasional, tidak semata-mata karena Indonesia memang membutuhkan undang-undang hak cipta. Pada tahun-tahun awal kemerdekaan bahkan tidak ada satupun lembaga negara baik lembaga pemerintah, eksekutif maupun lembaga-lembaga tinggi (maupun tertinggi) negara lainnya yang peduli dengan keadaan itu. Padahal pada waktu itu negeri ini sangat membutuhkan ilmu pengetahuan, guna memajukan peradaban yang dilindungi dengan instrumen hak cipta. Bidang sinematografi yang di dalamnya sarat dengan pesan peradaban juga luput dari perhatian penyelenggara negara ketika itu. Padahal sejarah mencatat Indonesia, India dan Amerika memulai industri perfilmannya tidak terpaut dalam rentang waktu yang jauh.182 Jika Indonesia memulai industri perfilmannya tidak terpaut jauh dengan kedua negara tersebut, mengapa perfilman Indonesia jauh tertinggal dibandingkan kedua negara tersebut?. 180 Lebih lanjut lihat Robert Gilpin, Global Political Economy Understanding The International Economic Order, Princeton University Press, New Jersey, 2001 dan Lynn H. Miller, Agenda Politik Internasional, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006. 181 Tanah-tanah dan hutan di pinggir laut, di kaki gunung begitu mudah diaih fungsi, yang semula adalah hutan atau tanah ulayat, kemudian berubah menjadi hak-hak atas tanah menurut UUPA No. 5 Tahun 1960 untuk dan atas nama pengusaha. Modusnya adalah dengan membuat terlebih dahulu peraturan perundang-undangannya. Sebaliknya tanah-tanahyang semula diterbitkan dengan Hak Milik atau Hak Guna Bangunan menurut UUPA dengan diikuti berbagai kewajiban seperti pembyaran pajak berupa PBB dan BPHTB, justeru ketika akan dimanfaatkan sesuai hak yang diberikan undang-undang justeru tak bisa dimanfaatkan, karena oleh pejabat Pemkab atau pejabat Pemko dinyatakan sebagai jalur hijau. Anehnya jalur hijau itu boleh dan dapat dirobah jika diusulkan perubahannya kepada pemerintah kota atau pemerinta kabupaten. Untuk dan atas nama peraturan perundang-undangan “kekuasaan absolut” para eksekutif dibungkus dengan rapi. 182 Indonesia memulai Industri filmnya pada tahun 1926, India memulai industri filmnya pada tahun 1913 dan Amerika memulai industri filmnya pada tahun 1894. 267 Undang-undang yang dilahirkan itu haruslah mewakili kehendak rakyat bukan kehendak pemerintah semata. Jika dalam sebuah undang-undang yang dilahirkan itu masih saja menunjuk pada kewenangan pemerintah yang begitu besar, maka undang-undang yang dilahirkan itupun bisa menjelma menjadi undang-undang yang menjustifikasi “negara kekuasaan”. Dalam undang-undang Hak Cipta Nasional dapat diukur seberapa banyak pasal-pasal dalam undangundang tersebut yang masih menunjuk pada pemerintah untuk pelaksanaan undang-undang tersebut. Matrik di bawah ini menjelaskan tentang masih diberikannya peranan eksekutif oleh Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002. Matrik 30 Kewenangan Eksekutif Untuk Membuat Peraturan Pelaksana Undang-undang No. 19 Tahun 2002 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pasal Pasal 10 ayat (4) Pasal 25 Pasal 28 ayat (2) Pasal 47 ayat (4) Pasal 48 ayat (4) Pasal 54 Materi Yang Diatur Ketentuan mengenai hak cipta yang dipegang oleh Negara Informasi tentang manajemen hak pencipta Tentang produksi yang menggunakan cakram optik Tentang pencatatan perjanjian lisensi Tentang anggaran biaya dewan hak cipta Biaya pencatatan lisensi Sumber : Diolah dari Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Matrik di atas memperlihatkan bahwa undang-undang ini memberi kewenangan untuk membuat peraturan kepada pihak eksekutif. Peraturan yang baik dalam konsep negara hukum, mestilah dilahirkan oleh lembaga yudikatif bukan oleh lembaga eksekutif. Eksekutif adalah pelaksana undang-undang (baca : peraturan) bukan pembuat peraturan, sekalipun peraturan itu merupakan peraturan organik sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang, akan tetapi jika peraturan yang dibuat oleh eksekutif terlalu banyak maka kekuasaan legislatif akan bergeser kepada pihak eksekutif, yang pada gilirannya akan menciptakan negara kekuasaan bukan negara hukum. 268 Jika dibandingkan dengan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 yang hanya menunjuk satu pasal saja yang memberikan kewenangan kepada eksekutif untuk membuat peraturan pelaksana yakni mengenai dewan hak cipta yang diatur dalam Pasal 39 ayat (3). Menguatnya kekuasaan eksekutif dapat juga dilihat dari ketentuan Pasal 10 jo. Pasal 31 Undang-undang No. 19 Tahun 2002. Pasal ini menegaskan bahwa : negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya. Negara juga memegang hak cipta atas foklor dan hasil kebudayaan yang menjadi milik bersama, seperti cerita hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya. Negara dalam konteks ini diposisikan sebagai owner atau pemilik. Jika dihubungkan dengan konsep negara, maka sesungguhnya negara hanya berfungsi sebagai badan penyelenggara administrasi pemerintahan. Mengacu kepada konsep ini, seyogyanya negara tidak hanya tidak diperkenankan membuat hak baru (negara hanya mengesahkan hak yang ada) tapi juga lebih jauh negara tidak boleh mengambil alih hak dan bahkan menjadi owner dalam setiap hak yang ada dan yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat Indonesia baik hak itu lebih dulu ada sebelum negara ini didirikan maupun setelah negara ini berdiri. Ketentuan Pasal 10 yang menyatakan bahwa negara menjadi pemegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan budaya nasional lainnya serta pemegang hak cipta atas foklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, menunjukkan betapa negara ini tampil sebagai subyek penguasa yang mengambil alih hak yang sesungguhnya dilahirkan bukan untuk dan atas nama negara. Bahwa hak tersebut belum diketahui siapa pemiliknya, itu adalah persoalan lain. Akan tetapi seyogyanya negara hanya boleh menjalankan fungsi sebagai alat atau badan yang memposisikannya sebagai subyek hak menguasai bukan sebagai pemegang hak yang dalam terminologi undang-undang hak cipta sebagai pemilik. Menguatnya hak negara untuk obyek hak cipta sebagaimana dimaksudkan di atas dikukuhkan lagi dengan norma yang mengatakan bahwa untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut, khusus bagi orang asing terlebih dahulu harus mendapat izin dari instansi yang berhubungan dengan masalah itu. Kata instansi menyebabkan perizinan itu kembali kepada kekuasaan negara bukan 269 kepada rakyat yang melahirkan kebudayaan yang menghasilkan karya cipta milik bersama tersebut. 183 Kewenangan negara menjadi lebih besar lagi atas obyek karya cipta sebagaimana dimaksudkan di atas ketika Pasal 31 ayat (1) menegaskan dan memperkuat tentang tidak adanya batas waktu penguasaan hak cipta semacam itu. Ini adalah situasi normatif yang buruk ketika negara diposisikan sebagai owner bukan sebagai subyek hak menguasai negara. Undang-undang Hak Cipta Nasional yang berpangkal pada Undang-undang No. 6 Tahun 1982 sebagai undang-undang yang menggantikan Auteurswet 1912 Stb. No. 600 peninggalan Kolonial Belanda, adalah undang-undang yang dapat dikatakan menyahuti aspirasi masyarakat Indonesia. Sejarah penyusunannyapun melalui tahapan akademik dengan didahului dari berbagai masukan dari pihak pencipta, penerbit, komponis, penyanyi, produser serta kalangan seniman dan asosiasi-asosiasi yang menghimpun aktivitas mereka. Catatan sejarah kelahiran Undang-undang No. 6 Tahun 1982 cukup memberikan penguatan secara akademik bahwa Undang-undang No. 6 Tahun 1982 meskipun dilahirkan di bawah rezim orde baru, undangundang ini dapat dikatakan cukup aspiratif. Secara ketatanegaraan, undang-undang inipun memuat tiga landasan pokok yang diperlukan dalam penyusunan undang-undang yakni landasan ideologis-filosofis, landasan yuridis-normatif dan landasan politis-operasional. Dalam konsiderans Undang-undang No. 6 Tahun 1982 dapat dibaca bahwa sebagai landasan filosofis, penyusunan undang-undang ini adalah Pancasila. Landasan yuridis normatif adalah Undang-undang Dasar 1945 serta landasan politis adalah TAP MPR No. IV Tahun 1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. 184 Undang-undang inipun menegaskan bahwa pengaturan tentang hak cipta yang diatur dalam Auteurswet 1912 Stb No. 600 sudah tidak 183 Misalnya sebuah tarian koreografi yang banyak dilahirkan oleh Kesultanan Negeri Serdang namun tarian itu dibuat dan dilahirkan dengan kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat yang mempunyai apresiasi terhadap dunia seni. Jika tarian koreografi itu akan diperbanyak atau diproduksi oleh orang yang bukan warga negara Indonesia maka izinnya tidak diberikan oleh Kesultanan Negeri Serdang bersama masyarakat adatnya, akan tetapi diberikan oleh instansi terkait dalam masalah itu. Tidak dapat dibayangkan jika kemudian tanpa sepengetahuan Kesultanan Negeri Serdang dan masyarakat hukum adatnya karya koreografi tersebut kemudian diperbanyak oleh warga negara asing hanya karena yang bersangkutan mendapat izin dari instansi yang terkait. 184 Lihat lebih lanjut bahagian menimbang huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 15 tanggal 12 April 1982. 270 sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita nasional dan karenanya harus dicabut dan digantikan dengan Undang-undang Hak Cipta Nasional sesuai dengan politik pembangunan hukum nasional negara Republik Indonesia. Sisi humanis atau sisi kemanusiaan lebih banyak tergambar dalam undang-undang ini, misalnya saja agar hasil karya cipta itu dapat dinikmati juga oleh orang lain pembatasan jangka waktu kepemilikan hak cipta dibatasi sampai selama hidup pencipta ditambah dengan 25 (dua puluh lima) tahun setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Ini berbeda sekali dengan Auterurswet Stb 1912 No. 600 yang memberikan hak sampai dengan 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia sehingga aspek sosial dari pemanfaatan hak cipta itu baru dapat terealisasi setelah 50 (lima puluh) tahun pencipta meninggal dunia. Sisi kemanusiaan undang-undang ini masih tergambar dalam undang-undang hak cipta yang terakhir yakni Undang-undang No. 19 Tahun 2002. Nilai-nilai kemanusiaan lainnya yang tergambar dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002 adalah Pasal 15, 16 dan 23.185 Intinya adalah untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan, hak cipta boleh digunakan tanpa harus meminta ijin dari pencipta, namun dengan syarat sumbernya harus disebut dan tidak merugikan kepentingan yang wajar terhadap pencipta atau pemegang hak cipta. Sebagai suatu bangsa yang hari ini sedang mengalami situasi politik dan penegakan hukum yang belum menggambarkan cita-cita negara hukum, agaknya sudah saatnya untuk mencermati kembali komitmen bernegara sebagai negara hukum. Era globalisasi, patut untuk dicermati sebagai titik awal untuk memulai penegakan hukum yang berkeadilan sarat dengan landasan etis dan moral. Penegasan ini bukanlah tidak beralasan, selama kurun waktu lebih dari tiga dasawarsa 185 Pasal 15 berisikan ketentuan tentang kebolehan untuk menggunakan hak cipta orang lain guna kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah, keperluan pembelaan didalam atau diluar pengadilan, ceramah yang semata-mata digunakan untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan, pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran, untuk keperluan para tunanetra yang tidak bersifat komersial dengan catatan harus menyebutkan sumbernya dan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Pasal 16 berisikan tentang lisensi wajib guna kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan. Pasal 23 memberikan kewenangan kepada pemilik hak cipta atas ciptaan fotografi, seni lukis, gambar, arsitektur, seni pahat dan atau hasil seni lain tanpa persetujuan pemegang hak cipta untuk mempertunjukkan ciptaan didalam suatu pameran untuk umum atau memperbanyak dalam satu katalog. 271 bangsa ini hidup dalam ketakutan, ketidak pastian hukum dan hidup dalam intimitas (suasana keakraban) yang tidak sempurna antara sesama warga masyaraka, sebuah solidaritas sosial yang semu. Di sisi lain perjuangan serta kemampuan bangsa ini untuk menciptakan iklim penegakan hukum yang berkeadilan sering kandas di tangan anak bangsa - yang berkuasa - sendiri. Apa yang sesungguhnya yang dialami tidak lain adalah pencabikan moral bangsa sebagai akibat dari kegagalan bangsa ini dalam menata manajemen pemerintahannya yang berlandaskan hukum. Tidak ada negara didunia ini yang begitu luas dampak pelanggaran hukumnya dalam struktur pemerintahannya ; mulai dari tingkat pemerintahan pusat sampai tingkat pemerintahan desa dan merambah jauh ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat lokal yang dikenal taat dalam menegakkan adat istiadat, etika religius yang ditandai dengan runtuhnya rasa kebersamaan dan hilangnya rasa saling menghormati dan saling menghargai antara sesama warga. 186 Dalam konteks undang-undang hak cipta nasional bila dihubungkan dengan penjelasan Pasal 12 huruf k Undang-undang No. 19 Tahun 2002 mengisyaratkan bahwa karya sinematografi yang merupakan media komunikasi gambar gerak (moving images) tidak hanya merupakan karya film layar lebar dengan skenario atau karya sinematografi elektronik yang ditayangkan di televisi atau media lainnya, tetapi juga meliputi karya berupa film iklan dan reportase yang dibuat tanpa skenario. Karya-karya ini ditonton oleh ribuan bahkan jutaan warga di tanah air dan pesan yang disampaikan oleh karya sinematografi ini beragam makna. Sebagai sebuah karya peradaban, karya sinematografi ini juga berdampak pada pembentukan karakter bangsa. Tidak jauh berbeda dengan karya sinematografi yang berasal dari negara asing, yang dalam berbagai pesannya melukiskan peristiwa kekerasan, seks bebas, peperangan, politik yang curang, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, horor dan sedikit sekali menampilkan 186 Mulai dari kasus korupsi yang melibatkan petinggi-petinggi negara di Republik ini sampai dengan kasus narkoba dan geng motor yang melibatkan kelompok kelompok miskin di perkotaan. Mulai dari penjarahan uang bank yang melibatkan para politisi, pengusaha, pejabat negara sampai pada penjarahan satu atau dua janjang kelapa sawit yang melibatkan rakyat kecil yang tinggal di pinggiran kebun-kebun milik Perkebunan Negara dan Swasta Asing. Khusus mengenai pelanggaran hak cipta, bidang karya sinematografi tak pelak lagi kita dapat menyaksikan di pasar-pasar tradisional dan di pinggiran jalan bahkan di depan kantor polisi secara terang-terangan dipasarkan DVD dan VCD hasil pelanggaran hak cipta yang melibatkan banyak pihak, mulai dari para pengganda sampai pada konsumen yang membeli hasil karya cipta yang diproduksi dengan cara melawan hukum tersebut. Ungkapan ini menggambarkan betapa buruknya situasi pelanggaran hukum di negeri ini. 272 nuansa drama rumah tangga yang mendidik, cerita tentang keindahan alam sebagai ciptaan Sang Maha Kuasa yang kesemua ini berujung pada pembentukan karakter anak-anak bangsa yang jauh dari cita-cita pembangunan kebudayaan nasional. Film-film cerita, bahkan iklan serta hasil reportase yang ditayangkan lewat media elektronik di Indonesia telah juga turut mempengaruhi pembentukan karakter masyarakat Indonesia. Cerita-cerita film, sinematografi elektronik (sinetron) reportase, iklan, yang mempertontonkan rumah mewah, mobil mewah, jabatan tinggi, pengusaha sukses, perselingkuhan dan sederetan pesan-pesan yang menegasikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia saat ini tidak lagi bisa dan dapat dihempang. Terdapat banyak ketidak jelasan dalam format pembangunan kebudayaan (sebagai politik kebudayaan yang didalamnya termasuk bidang hukum sebagai sub sistem politik) nasional, sejak awal Republik ini didirikan sampai saat ini. Di sisi lain Undang-undang No. 19 Tahun 2002 justru mengisyaratkan sengketa perdata dalam hak cipta telah digiring untuk diadili di Pengadilan Niaga (vide Pasal 58 Undang-undang No. 19 Tahun 2002) dan sekalipun telah diberi ruang untuk diadili di Lembaga Arbitrase yang memungkinkan untuk dimasukkannya unsur-unsur adat dan yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai filsafat Pancasila yang merupakan abstraksi dari the original paradigmatic value of Indonesian culture and society, namun tradisi peneyelesaian sengketa melalui lembaga Peradilan Formal, tetap menjadi pilihan. Pada bahagian lain tidak arif ketika Undang-undang No. 19 Tahun 2002 memasukkan klausule normatif yang memberikan kewenangan kepemilikan atau owner kepada negara terhadap hak cipta peninggalan sejarah-sejarah dan budaya nasional serta hak cipta hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama. Tidak arif juga ketika ada pihak lain (yang bukan Warga Negara Indonesia) yang akan memperbanyak atau mengumumkan ciptaan tersebut harus mendapat izin dari instansi pemerintah tetapi justru bukan pada kelompok masyarakat yang melahirkan karya cipta tersebut. Adalah lebih baik dan lebih arif ketika hak semacam itu kepemilikannya (pemegang hak cipta) diserahkan kepada masyarakat hukum adat yang memahami seluk beluk hak-hak tradisional dan hak-hak kolektif. Memang sandungan budaya dan intervensi politik dalam praktek penegakan hukum adalah sesuatu yang tak terelakkan sepanjang sejarah Negara Indonesia merdeka dan terus berlangsung sampai hari ini. Namun, kearifan para aparat penegak hukum senantiasa dituntut agar dapat menyahuti hati nurani rakyat sebagai pencerminan 273 dari ideologi Pancasila sebagai landasan moral bangsa, sekalipun belum diwujudkan dalam bentuk aturan hukum normatif. Ada perubahan yang terjadi dalam masyarakat sebagai suatu kesadaran baru saat ini yakni ; kaum lemah dan tak berkuasa tidak lagi bersedia menerima kemiskinan dan ketidak adilan secara pasif ; dan suara amarah mereka mengganggu serta mengancam pihak-pihak yang bermaksud mempertahankan status quo. Pada saat ketidak adilan menjadi tak tertanggungkan lagi oleh masyarakat, yang apda akhirnya membuahkan tindakan kekerasan di mana-mana. Keadilan menjadi syarat mutlak bagi kelangsungan bangsa ini ke depan. Ada asumsi yang kuat bahwa kelangsungan negara ini ke depan bukan semata-mata karena keberhasilan pembangunan dalam bidang ekonomi. Kehancuran dan sejarah jatuhnya negara-negara besar di dunia termasuk runtuhnya kepemimpinan Orde Baru adalah dipicu oleh ketidak adilan bukan oleh faktor kegagalan dalam pembangunan ekonomi. 187 Faktor utama ketidak adilan itu muncul adalah karena materi hukum yang dirumuskan oleh lembaga legislatif tidak aspiratif atau tidak dapat menyahuti tuntutan masyarakat atau dalam rumusan lain hukumnya tidak responsif. 188 Jika hukum tidak responsif, maka ia akan kehilangan "rohnya". Rohnya hukum itu adalah moral dan keadilan. Moral dan keadilan begitu mudah ditemui dalam hati nurani rakyat, maka undang-undang hak cipta nasional harus disesuaikan dengan tuntutan hati nurani rakyat tersebut, tidak semata-mata disesuaikan dengan TRIPs Agreement. Penyesuaian undang-undang hak cipta nasional yang terakhir adalah Undang-undang No. 19 Tahun 2002, haruslah melihat kembali pada tatanan moralitas yang hidup dan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Era dimana hukum 187 Selama kurun waktu pemerintahan Orde Baru, telah berhasil meningkatkan PDB domestik dengan laju pertumbuhan ekonomi 5 s/d 7 % per tahun, dan pada akhir Repelita VI secara mengejutkan berhasil menekan angka rakyat miskin sampai dengan 20% dari 200 juta penduduk Indonesia. Namun oleh karena ketiadaan pemerataan (instrumen hukum, gagal mencapai keadilan) kesenjangan ekonomi dengan dikotori kaya miskin membuat keadaan semakin buruk yang akhirnya mendadak sontak ketika George Soros dengan "Money Business"-nya di awal kejatuhan Orde Baru mengantarkan penduduk Indonesia jatuh miskin menjadi lebih dari 60% dipenghujung tahun 1998. Lemahnya fondasi ekonomi Indonesia tak pelak lagi karena instrumen hukum perbankan tidak mendukung kearah terciptanya lembaga keuangan yang kuat. 188 Lebih lanjut lihat Philippe Nonet, Philip Selznick, Toward Responsive Law & Society in Transition, Transaction Publishers, USA & London, 2009. Lihat juga Satjipto Rahardjo, Hukum Progrresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Genta Publishing, Jakarta, 2009, Satjipto Rahardjo, Membangun dan Merombak Hukum Indonesia Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009. 274 dibangun atas kehendak penguasa (top down) sudah berakhir. Suarasuara rakyat yang tumbuh dari bawah (buttom up) sudah tiba waktunya untuk disahuti, dengan merumuskannya dalam berbagai kebijakan atau wawasan politik hukum yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Nasional, baik itu dalam Rencana Pembangunan Jangka Pendek, Menengah ataupun Jangka Panjang, selaku dokumen politik hukum. Kesemua ini dimaksudkan, agar hukum tidak kering dari nilai-nilai kultural bangsa Indonesia yakni nilai kemanusiaan dan pada gilirannya menumbuhkan sikap bahwa semua warga negara berhak untuk mendapat penghormatan atas marwah kemanusiaannya yang kesemua itu akan berujung pada kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum sekaligus kepatuhan pada pemimpin (protogonis) yang menjadi karakter anak bangsa. D. Perubahan dan Pergeseran Nilai Kebangsaan Semangat yang melahirkan faham kebangsaan atau semula dirumuskan sebagai spirit Nasionalisme, berpangkal pada pergolakan kebangkitan Dunia Timur pada penghujung abad XIX dan awal abad XX di panggung politik Internasional. Diawali dari perjuangan Yose Rizal di Philipina (1898), demikian tulis Kaelan 189 dan kemenangan Jepang atas Rusia di Tsunia (1905), Sun Yat Sen di Cina (1911), dan diikuti dengan pergerakan nasionalisme di India olek Tilak dan Mahatma Gandhi denganPartai Kongresnya dan menyusul Indonesia pada tahun 1908 yang dipelopori oleh Wahidin Soedirohoesodo dengan Budi Utomonya. Gerakan inilah yang memelopori gerakan nasionalis untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa. Bangsa yang bermarwah, bermartabat dan berdiri di atas kekuatan sendiri tanpa intervensi Asing. Semangat kebangsaan itu terus berkobar dalam jiwa dan sanubari rakyat Indonesia hingga sampai ke fase kemerdekaan dan kemudian dituangkan dalam ideologi negara yakni Pancasila dengan menempatkannya dalam sila ke tiga yakni Persatuan Indonesia, yang sebelumnya diusulkan Bung Karno dengan nama Naionalisme. Inti dari kata “persatuan Indonesia” dimaknai secara dinamis, yakni suatu proses atau dinamika yang melahirkan bangsa dan negara Indonesia yakni proses untuk menyatukan wilayah, bahasa, agama, suku, adat istiadat dan segala macam perbedaan dalam masyarakat Indonesia yang pelural. Hanya dengan persatuan itulah masyarakat Indonesia, dapat menjadi kokoh, kuat dan mampu berdiri di atas kaki sendiri. 189 Kaelan, Op.Cit, hal. 16-17. 275 Adagium “bersatu kita teguh bercerai kita rubuh” adalah sebuah adagium yang mengisyaratkan betapa pentingnya arti persatuan. Sila-sila dalam Pancasila itu harus di tempatkan secara hirarkhis dalam satu piramidal, sehingga sila pertama menjiwai silasilai yang lain yang ada di bawahnya. Sedangkan sila kedua dijiwai oleh sila pertama, menkjiwai sila ketiga dan seterusnya. Sehingga sila ketiga dijiwai oleh sila pertama dan menjiwai sila ke empat dan kelima. Dalam kontes ini maka Perstauan Indonesia dijiwai oleh Sila Ketuhanan dan sila Kemanusiaan dan menjiwai sila Kerakyatan dan sila Keadilan sosial. Sehingga kedudukan sila ketiga ini menjadi sangat penting sebab djiwai oleh dua sila di atasnya dan menjiwai dua sila di bawahnya. Tidak ada artinya persatuan Indonesia, jika persatuan itu tidak membawa makna Ketuhanan dan Kemanusiaan. Tidak juga menjadi bermakna sila Kerakyatan dan Keadilan Sosial jika tidak ditempatkan dalam Persatuan Indonesia. Negara akan berada pada posisi yang kuat jika , nilai Persatuan itu dijadikan dasar kebijakan penyelenggaraan negara, termasuk dalam menetukan pilihan politik hukum. Khusus dalam pilihan kebijakan politik hukum justeru jangan sampai pada titik tertentu, hukum yang dilahirkan justeru menimbulkan perpecahan di kalangan anak bangsa. Misalnya hukum yang dilahirkan itu justeru diskriminatif, misalnya hak untuk orang kaya berbeda dengan hak untuk orang miskin dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan. Atau hukum yang dilahirkan menyamakan semua kewajiban, misalnya perlakuan untuk nilai ujian negara atau masuk perguruan tinggi untuk seorang anak yang bersekolah di desa dengan fasilitas sederhana disamakan nilainya dengan seorang anak yang bersekolah di kota besar dengan fasilitas yang lengkap. Hukum semacam ini akan menimbulkan perpecahan, kering dari rasa keadilan, jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan ini akan mengancam Persatuan Bangsa dan melemahkan semangat nasionalisme. Bung Karno sendiri ingin menempatkan sila Persatuan Indonesia itgu pada sila pertama, yang kala itu dirumuskannya sebagai sila Kebangsaan, karena pentingnya arti persatuanitu dalam konsep pemikirannya. Hal itu dapat dimaklumi karena perjalanan untuk memerdekakan bangsa itu sering kandas karena banyaknya perpecahan di kalangan anak bangsa sendiri. Oleh karena itu dengan sangat etis dan sangat hati-hati Bung Karno 190 mengumandangkan maksud itu dalam pidatonya : 190 Kaelan, Op.Cit, hal. 262-263. 276 Kita mendirikan satu negara kebangsaan Indonesia. Saya minta saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo (dari golongan Islam) dan saudara-saudara Islam lain, maafkanlah saya memakai perkataan “Kebangsaan” ini. Sayapun orang Islam, tetapi saya minta kepada saudara-saudara, janganlah saudara-saudara salah faham jikalau saya katakana bahwa dasar pertama buat Indonesia ialah dasar kebangsaan. Itu bukan berarti satu kebangsaan dalam arti yang sempit, tetapi saya menghendaki satu nationale staat, seperti yang saya katakana dalam rapat di Taman Raden Saleh beberapa hari yang lalu. Satu Nationale Staat Indonesia bukan berarti staat yang sempit. Kehati-hatian Bung Karno itu, karena golongan Islam, ingin menjadikan Islam sebagai Dasar Negara atau paling tidak bagai jumat islam berlaku syari’at Islam. Akan tetapi Bung Karno melihat, adalah suatu klenyataan bahwa masyarakat Indonesia tidak semuanya beragama Islam, untuk menghindari perpecahan, Bung Karno menawarkan sila Kebangsaan atau Persatuan sebagai sila yang diletakkan sebagai dasar pertama. Persatuan Indonesia itu sebenarnya lebih dimaksudkan dalam konstelasi kedaulatan negara, ketimbang unsur negara, begitu analisis M.Yamin terhadap pidato Bung Karno itu. Yamin 191 menguraikan soal persatuan nasional ini dalam kaitannya dengan apa yang disebutnya sebagai E’tat nation, nationale state, negara kebangsaan’, yang mensyaratkan ‘kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar’. ‘Kedaulatan ke dalam, memberikan perlindungan dan pengawasan pada putra negeri. kedaulatan ke luar, kesempatan luas mengatur pertaliannya dengan negara lain. Dalam konteks hubungan dengan negara lain, kedaulatan ke luar itulah yang menjadi inti penting faham kebangsaan. Apakah di kemudian hari dengan mengikat hubungan atau kerja sama dengan negara lain, kedudukan negara semakin menguat atau semakin melemah di mata dunia Internasional. Atau justeru hubungan ke luar dengan negara lain justeru menciptakan model emperilais baru, emperialis modern yang terselubung. Hal itu dapat terjadi bila ketergantungan negara semakin besar dengan negara lain, apakah itu karena disebabkan bantuan atau pinjaman luar negari, atau karena bantuan militer dan keamanan. Ketergantungan dan kemandirian suatu bangsa kerap kali berhubungan dengan menguat atau melemahnya nilai-nilai kebangsaan yang melekat dalam jiwa rakyatnya. Mereka yang sadar akan arti berbangsa akan terus melakukan aktivitasnya demi negara dan bangsanya. Selalu meletakkan kepentingan bangsa di atas kepentingan individunya sendiri. Ketika rakyatnya memiliki peluang untuk melakukan korupsi, ia tidak akan melakukan itu, karena itu akan 191 Ibid, hal. 63. 277 merugikan bangsanya sendiri. Ketika ada fasilitas umum yang berpeluang untuk dikuasai atau dimanfaatkannya untuk kepentingan dirinya sendiri, ia tidak akan melakukan itu karena tindakan itu akan merugikan bangsanya sendiri. Demikian juga ketika akan melakukan hubungan dagang dengan bangsa lain dengan mengorbankan sumber daya alam yang ada di negaranya, hubungan dagang itu tidak diteruskan karena akan merugikan bangsanya sendiri. Mengikat kerjasama dengan negara lain dalam bentuk instrumen hukum Internasional seperti Konvensi atau perjanjian bilateral (traktat) negara tidak melakukannya, jika kesepakatan Internasional itu merugikan bangsanya sendiri. Itulah hakekat faham kebangsaan. Jika faham kebangsaan ini dihubungkan dengan konsep negara hukum, maka hukum harus bersumber pada asas kebangsan. Politik hukumlah yang kemudian mengarahkan bagaimana nilai-nilai kebangsaan itu diturunkan dalam bentuk asas-asas hukum (tata nilai). Dalam proses selanjutnya hukum menjadi produk politik yang menyahuti nilai-nilai kebangsaan itu. Akan tetapi dalam negara hukum, hukum harus determinan terhadap politik, artinya hukum harus menjadi variabel yang mempengaruhi (independent variabel) terhadap politik, tidak boleh sebaliknya justeru politik yang determinan terhadap hukum, sehingga politik menjadi variabel mempengruhi (independent variabel) dan hukum menjadi variabel terpengaruh (dependent variabel). Jika yang terakhir ini terjadi maka negara yang bersangkutan bukan negara hukum, tetapi negara kekuasaan. Sekalipun hukum adalah produk politik, akan tetapi sebelum nenjadi hukum, kekuasaan politik itu diberikan oleh hukum, sehingga aktivitas legislasi dilakukan benarbenar menurut hukum dan hukum tertinggi (grund norm) dijadikan dasar dalam aktivitas legislasi. Dengan demikian supremasi hukum akan dapat ditegakkan sesuai dengan konsepsi negara hukum. Menghubungkan nilai kebangsaan dengan politik, menggiring pemikiran bahwa dalam kebangsaan terdapat kehendak rakyat dan rakyat diwakili oleh elit politik yang kemudian duduk di kursi legislatif melahirkan hukum dalam arti formal antara lain dalam nemtuk undangundang. Akan tetapi benarkan undang-undang itu mewakili suara rakyat ? Dalam suatu negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokratis, badan legislatif yang diwakili oleh elit politik adalah representatif dari suara rakyat. Sehingga persepsi yang selama ini terbangun adalah dalam sebuah negara demokratis, pemerintahan diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Akan tetapi 278 merujuk pada studi yang dilakukan oleh Mahfud MD 192 ternyata tereduksinya arti demokrasi dari, oleh dan untuk rakyat menjadi pemerintahan dari rakyat, oleh elit dan untuk elit. Itulah sistuasi yang terjadi selama kurun waktu pembentukan dan pemberlakuan undangundang hak cipta nasional. Sehingga Lev, 193 menyarankan lebih seringlah menggunakan istilah Republik daripada istilah Demokrasi. Istilah republik lebih berkonotasi pada kepentingan rakyat, sedangkan istilah demokrasi lebih mengedepankan pada simbol absolutisme kekuasaan rakyat dalam menetukan sesuatu namun selalu dikontrol oleh kepentingan politik tertentu. Setelah ratifikasi GATT 1994/WTO yang di dalamnya memuat TRIPs Agreement Indonesia sudah melangkahkan kakinya ke dalam ikatan negara-negara industri maju yang ekonominya bertumpuh pada kekuatan HKI. Bidang industeri manufactor dan jasa adalah sektor terbesar yang menyumbang ekonomi Amerika di luar sektor pertanian. Industeri senjata menempati peringkat pertama sedangkan industeri perfilman (sinematografi) menempati urutan kedua, menyusul industeri otomotif, tekstil dan industeri dalam bidang elektronik. Mulai dari Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri sampai pada sirkuit terpadu. Industri-industri itu kesemuanya bertumpu pada HKI. Itulah sebabnya Amerika begitu bersikukuh memperjuangkan HKI nya agar mendapat perlindungan yang kuat di luar negaranya, melalui organisasi perdagangan dunia. Ketergantungan Indonesia dengan negara-negara ekonomi maju yang diikuti dengan pasokan pinjaman atau hutang luar negeri tidak terlepas dari keinginan awal negara-negara di dunia untuk mendirikan organisasi perdagangan internasional (international trade organization) yang telah diprakarsai sejak tahun 1947 yang kemudian berubah menjadi World Trade Organization (WTO). Padahal sejak awal negara-negara yang diajak untuk bergabung dalam WTO itu tidak memiliki kesetaraan dalam sumber ekonomi, yang meliputi aspek permodalan, keahlian, dan ketersediaan sumber daya alam. Ketika negara-negara ini diajak untuk bergabung dalam WTO masing-masing pihak dengan berbagai perbedaan itu tidak dapat menyampaikan keinginannya secara utuh. Hal ini disebabkan karena masih terdapat kualitas ketidak mandirian dari masing-masing negara merdeka dan berdaulat yang akan bergabung dalam WTO. Ini yang oleh Justice 192 Mahfud MD dalam kata pengantarnya Daniel S. Lev., Hukum dan Politik di Indonesia Kesinambungan dan Perubahan, LP3ES, Jakarta, 1990, hal xiii. 193 Ibid, hal. xii 279 Jackson disinyalirnya sebagai sebuah kerjasama yang sulit untuk mencapai sukses kecuali kesepakatan hukum yang dibuat itu dapat melawan apa yang lebih memberikan keuntungan. Negara yang merdeka dan berdaulat dan benar-benar independen yang dapat melepaskan diri dari ketergantungan. Hukum yang memuat kesepakatan internasional sebaiknya menghormati doktrin kesetaraan. Akan tetapi kesetaraan itu sulit untuk diwujudkan jika sejak awal telah didesain agar negara-negara berdaulat itu menjadi tergantung baik secara ekonomi maupun secara politis.194 Dengan meminjam pandangan Gunder Frank, Sritua Arif dan Adisasono menegaskan bahwa : “Hubungan ekonomi diantara negara maju dengan negara berkembang dibangun dengan sistem kapitalis dalam skala internasional”. 195 Hubungan yang tidak sehat itu dijadikan dasar untuk membangun tatanan ekonomi dunia di bawah sistem GATT/WTO. The funding fathers bangsa ini sejak awal berdirinya Republik Indonesia telah memikirkan dan berusaha agar negara ini berdiri sebagai negara yang kokoh. Berdikari, kata Bung Karno. 196 Bangsa ini mesti bisa berdiri di atas kaki sendiri. Negara harus kuat tak boleh lemah, jika tidak ingin didikte atau diombang-ambingkan oleh bangsa lain. 197 194 Philip C. Jessup , A Modern Law Nations (Pengantar Hukum Modern Antar Bangsa), Terjemahan Fitria Mayasari, Nuansa, Bandung, 2012, hal. 49. 195 Lebih lanjut lihat Sritua Arief & Adi Sasono, Indonesia Ketergantungan dan Keterbelakangan, Mizan, Jakarta, 2013, hal. 20. Pandangan Gunder Frank sebagaimana dikutip oleh Sritua Arief dan Adi Sasono menegaskan bahwa Gunder Frank menolak pandangan bahwa perkembangan ekonomi negara-negara miskin akan terjadi sebagai akibat hubungan ekonomi yang menimbulkan difusi modal, teknologi, nilai-nilai institusi dan lain-lain faktor dinamis. Berdasarkan penemuan-penemuan historis Gunder Frank di Amerika Latin, perkembangan yang sehat dan otonom justru terjadi pada saat tidak adanya hubungan antara negara maju atau menurut istilahnya metropolis dengan negara miskin atau negara satelit. Hubungan yang dibangun setelahnya justru membuat negara-negara maju menjadi penguasa ekonomi di negara-negara miskin tersebut yang berujung pada ketidak mandirian negara miskin tersebut. 196 Iman Toto K. Rahardjo, Herdianto WK, Bung Karno dan Ekonomi Berdikari, Grasindo, Jakarta, 2001. 197 Suatu kali, Malaysia pernah mencoba untuk mengusik kedaulatan Indonesia, Bung Karno langsung memberikan reaksi, dengan selogan ,”Ganyang Malaysia”. Berkali-kali Bung Karno dalam pidatonya yang mengisyaratkan agar bangsa ini melepaskan ketergantungan dengan bangsa lain. Go to hell with your aid. Apakah retorika politik Bung Karno itu kemudian menjadikan posisi Indonesia semakin buruk, Bung Karno tidak peduli. Pilihan keluar dari keanggotaan PBB pun Bung Karno sudah siap. Dengan segudang julukan yang ia miliki, seperti Pemimpin Besar Revolusi, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, pemerintahannya nyaris otoriter. Lupa membuat standarisasi kinerja birokrasi yang terukur, menciptakan perangkat hukum agar 280 Dalam pertarungan politik dan ekonomi global, saat ini penjelajahan pemahaman tentang berbagai faktor yang mengendalikan jalannya arus politik global itu tak dapat hanya ditelusuri melalui garis linier. Akan tetapi harus ditelusuri pula melalui garis non linier melalui bantuan berbagai disiplin ilmu. Dengan cara itu akan dapat diketahui mengapa suatu negara tampil menjadi negara yang sangat kuat, namun di sisi lain muncul negara yang sangat lemah, di bahagaian bumi di tempat lain muncul negara yang sangat kaya dan pada saat bersamaan di tempat lain muncul negara yang sangat miskin. Demikian pula di negara-negara di Eropa, di Asia Tenggara, di Timur Tengah dan di Indocina, muncul negara yang relatif bersih dari korupsi, tapi di negara lain muncul negara yang sangat tinggi angka korupsinya. Di berbagai negara dalam kawasan itu muncul negara yang sangat patuh terhadap penegakan bidang HKI nya, akan tetapi pada saat yang sama di negara lain yang masih bersama-sama berada dalam kawasan itu muncul negara dengan pelanggaran HKI yang tinggi. Setiap bangsa sebenarnya mempunyai harapan yang sama untuk mendapat posisi yang berharga di mata dunia dalam kehidupan bersama dengan bangsa lain. Pesan nilai “kebangsaan” diyakini sebagai pesan yang lahir dari bibit yang sama oleh tiap-tiap bangsa yang ada di dunia, sehingga sebenarnya tidak ada keunggulan suatu bangsa atas bangsa lain yang didasarkan pada pesan yang berharga dari nilai kebangsaan itu. Bangsa-bangsa di dunia seharusnya tumbuh bersama dengan bangsa lain dengan memanfaat potensi yang dimiliki bangsanya sendiri. Bahwa kemudian perbedaan dalam keberhasilannya mengelola potensi yang ada yang berpengaruh terhadap kesejahteraan di dalam negaranya itu adalah resultan dari pemahaman anak bangsanya dalam pengelolaan kehidupan nasionalnya. Garis batas yang telah disepakati oleh dunia Internasional adalah suatu bangsa tidak boleh mengintervensi kedaulatan negara lain. Penjajahan atas suatu bangsa terhadap bangsa lain tidak mungkin dapat lagi dilakukan seperti terjadi di masa lampau dan larangan itu telah dimuat dalam Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa. 198 kinerja lembaga negara menjadi teratur dan birokrasi pemerintahan menjadi berkualitas. Dengan menciptakan hukum demokrasi dapat dikawal. Mengawal hak-hak politik warga negara, melindungi hak milik individu, melindungi kehormatan warga negara kesemua itu itu dapat diukur dengan standar peraturan yang telah disepakati, tapi itu tidak dilakukan oleh Bung Karno. Bung Bung Karno larut dalam keasyikannya menjadikan politik sebagai panglima. 198 Lihat lebih lanjut, Hikmahanto Juwono, Op.Cit, hal. 5. Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB, berbunyi, “Nothing contained in the present charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic 281 Meskipun demikian bagi negara seperti Indonesia, tantangan yang dihadapi adalah tidak semata-mata datang dari luar, akan tetapi datang dari dalam (negeri) sendiri. Harus ada penguatan secara internal di dalam negeri, mulai dari penguatan birokrasi, sistem politik yang lebih menyuarakan republik, sistem penegakan hukum yang merujuk pada nilai-nilai atau grundnorm Pancasila, sistem pengelolaan ekonomi yang memihak pada kepentingan rakyat, sistem pendidikan yang membuka peluang kesempatan yang luas bagi rakyat untuk dapat mengecapnya sampai pada sistem pertahanan keamanan dan pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang berkeadilan. Secara simultan hubungan Internasional dibangun dengan pemahaman bahwa kebijakan lintas batas negara yang menjangkau jauh ke masa depan dapat dilaksanakan dengan meletakkannya dalam koordinasi manajmen internasional. Memang sangat sulit untuk dapat menjangkau itu tanpa kepiawaian berdiplomasi. Sangat sedikit lembaga yang berwenang di negeri ini yang mampu mengkoordinasikan masalah-masalah lintas batas yang menjangkau jauh ke depan itu dengan kebijakan dalam negeri. Kekeliruan dalam menyikapi ini, akan dapat berakibat fatal bagai suatu negara, karena sekalipun imperialism tidak lagi diperkenankan tapi karena kesalahan dalam mengambil langkah hasilnya tidak menutup kemungkinan terjadi imperialism tersembunyi. Imperialis yang halus yang lebih modern yakni melalui kebijakan hutang dan pinjaman luar negeri yang menciptakan ketergantungan atau melalui instrumen hukum internasional, seperti dalam kasus transplantasi UU hak cipta nasional yang mewajibkan Indonesia menyesuaikan peraturan perundang-undangan HKI nya dengan TRIPs Agreement. Kemajuan dalam teknologi komunikasi telah membuka pemahaman yang luas terhadap apa yang terjadi di satu negara begitu mudah untuk diketahui oleh belahan negara lain dalam hitungan detik. Sehingga dunia semakin terasa dekat namun disisi lain keadaan ini juga menimbulkan dampak negatif yang tidak sedikit, seperti semakin kompleksnya pertarungan akan sumber-sumber daya kehidupan. Semua ini akan berpengaruh pula pada pilihan-pilihan kebijakan yang ditempuh oleh satu negara sebagaimana diungkapkan oleh Koko 199 berikut ini : jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter, but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII”. 199 Ibid. 282 Peningkatan dalam produksi guna memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginan manusia menimbulkan masalah sampah, polusi dan penyalahgunaan sumber daya pada skala global. Perluasan kemampuan manusia untuk menyusup ke wilayah yang sebelum ini tidak terjangkau – lautan dalam, angkasa luar, gurun pasir yang terganas, pegunungan dan wilayah-wilayah es yang tak terjamah – telah menggeser daerah-daerah penyangga dan daerahdaerah netral yang dulu berfungsi sebagai pelunak dan peredam permusuhan. Pertumbuhan kekuatan destruktif yang berlipat ganda memperbesar kesulitan dalam pemeliharaan perdamaian – khususnya perkembangan sistem persenjataan yang semakin ringkas, dahsyat, mudah dibawa dan mudah didapatkan. Pembentukan dua gudang senjata nuklir besar, tidak hanya memberikan kemampuan pada negara-negara adidaya untuk melenyapkan peradaban manusia, tetapi juga mengubah hakikat politik internasional secara mendasar. Pemilikan persenjataan nuklir dipandang sebagai kartu masuk ke status adidaya. Bentuk-bentuk imperialisme modern sekalipun ditegaskan dalam piagam PBB tidak dibenarkan untuk dilakukan akan tetapi “unjuk pamer kekuatan senjata” negara-negara adidaya membuat negaranegara dunia ketiga seakan-akan tak mampu untuk mempertahankan kedaulatannya. Doktrin kedaulatan internasional yang dikembangkan pada abad pertengahan sebagaimana dikemukakan oleh Suhaidi200 didasarkan pada dua hal yang mendasar yaitu : (1) Pada satu segi kedaulatan timbul karena adanya kekhawatiran dari negara-negara nasional yang baru merdeka untuk menegaskan kemerdekaan total, termasuk pengembanan perekonomiannya, dan menghilangkan intervensi bangsabangsa feodal atau intervensi negara-negara besar. (2) Pada segi lain merupakan akumulasi dari negara-negara baru merdeka untuk membentuk hukum baru bagi pengaturan wilayahnya. Oleh karena itu, doktrin-doktrin kedaulatan negara itu memiliki relevansi dengan penelitian ini bahwa hukum-hukum baru yang dibentuk oleh negara yang berdaulat sebaiknya tidak mencerminkan intervensi kedaulatan negara asing terhadap kedaulatan negara lain. Negara-negara adidaya seringkali memanfaatkan situasi konflik dalam negeri untuk dan atas nama demokrasi turut melakukan penyerangan dan mengintervensi kedaulatan suatu negara. Contoh terakhir adalah bagaimana Amerika turut membantu melakukan serangan terhadap kediktatoran pemimpin Lybia. Meskipun ini tidak sepenuhnya untuk 200 Suhaidi, Perlindungan Lingkungan Laut : Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Laut Dengan Adanya Hak Pelayaran Internasional di Perairan Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Internasional, pada Falultas Hukum USU, tanggal 1 April 2006, hal.3. 283 menegakkan masyarakat yang demokratis karena dalam satu negara belum teruji juga bahwa sistem demokrasi adalah sistem yang paling tepat untuk mewujudkan kedamaian, kesejahteraan dan keamanan dalam negaranya. Untuk kasus Indonesia, Soedjatmoko 201 mengingatkan Laju perubahan demografi, ekonomi dan teknologi yang berlaku saat ini sedemikian rupa, sehingga empat puluh tahun yang akan datang akan menjanjikan tingkat ketidak stabilan yang sama, jika tidak lebih lagi dibanding empat puluh tahun sebelumnya. Lembaga-lembaga atau pengaturan-pengaturan baru manapun yang dibentuk saat ini bagi manajemen internasional kiranya juga dapat dianggap kadaluwarsa empat puluh tahun yang akan datang – atau bahkan pada saat lembaga-lembaga atau pengaturanpengaturan tersebut mulai berdiri atau diberlakukan. Tak satu kelompok pembuat keputusan pun yang memiliki kemampuan untuk menyusun semua fakta, memahami semua alternatif, memperkirakan semua reaksi atau mengantisipasi semua interpretasi dari suatu aksi. Kenyataan ini menuntut keluwesan yang maksimum, konsultasi yang seluas mungkin dan kerendahan hati yang besar dalam merancang sarana-sarana baru bagi manajemen sistem internasional. Koko mengajak, komponen-komponen bangsa ini harus dengan sikap rendah hati yang besar dengan kesadaran yang penuh bahwa, lembaga-lembaga negara dan sistem pemerintahan serta bentuk negara kesatuan yang dirancang pada tahun 1945 itu sudah daluwarsa untuk menghadapi arus globalisasi yang melanda peradaban dunia saat ini. Tantangan berikutnya harus ada keberanian untuk memberi makna pada nilai kebangsaan yang tidak hanya bersikukuh dengan faham negara kesatuan, akan tetapi membuka wacana lalu menggantikannya dengan bentuk negara federasi. Hal ini dimaksudkan untuk mengatasi ketidak stabilan dan kompleksitas yang merupakan ciri dari sistem internasional. Dengan Federasi faham kebangsaan akan tetap terpelihara ke dalam, dan keluar hubungan Internasional di bangun oleh pimpinan negara serikat yang juga dalam bentuk Republik. Keputusankeputusan politik untuk mengantisipasi perubahan atau sistem politik yang ditawarkan oleh manajemen internasional ditangani oleh pemerintah negara serikat, sehingga proses pembangunan dalam negeri tidak disibukkan dengan “urusan-urusan” internasional yang selalu bermuara pada ketidak pastian. Sistem pemerintahan dan bentuk negara kesatuan yang ada pada hari ini dengan sistem otonomi daerah, telah terkontaminasi dengan sistem manajemen internasioal yang kompleks dan penuh ketidak pastian itu. Akibatnya membawa dampak pada pilihan politik nasional yang cenderung tidak pasti juga. Dengan 201 Ibid, hal. 176-177. 284 federasi diharapkan dapat memberikan penguatan terhadap basis-basis lokal. Sistem otonomi daerah yang diturunkan dari bentuk negara kesatuan telah membuahkan rasa ketidak adilan di kalangan masyarakat, dan jika ini dibiarkan terus berlanjut akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Belajar dari kasus Srilanka dan India, pemberontakan Tamil adalah berpangkal pada ketidak adilan tersebut karena setiap kelompok masyarakat yang ada dalam satu negara selalu tidak puas atas pelayanan yang diberikan oleh negerinya. Kasus Aceh misalnya, berakhir pada pemberian otonomi khusus. Akan tetapi bukan tidak mungkin bagi Indonesia ke depan, kondisi ketidak adilan itu akan memicu konflik-konflik baru yang dapat menghancurkan nilai-nilai kebangsaan. Satu-satunya alternatif yang dapat dilakukan adalah bangsa ini harus dengan rendah hati dan sungguh-sungguh mengakomodasi kepentingan-kepentingan masyarakat lokal di daerahdaerah. Hal ini jelas lebih mudah untuk dilakukan dan sesungguhnya dapat dicapai sebelum pecah konflik bersenjata dan kekerasankekerasan yang memuncak akibat terpolarisasikannya berbagai sentimen yang melemahkan solidaritas kebangsaan untuk mengusahakan kompromi. Disinilah perlunya inovasi politik yakni dengan penuh kesantunan menggantikan badan-badan negara serta struktur pengelolaan birokrasi yang baru meninggalkan lembagalembaga lama yang dibentuk pada tahun 1945. Kekacauaan birokrasi, yang terjadi hari ini adalah karena kecenderungan memberi reaksi ke arah reduksionisme terhadap manajemen internasional. Salah satu perwujudan yang paling serius dari reduksionisme itu adalah ilusi bahwa satu-satunya pelaku yang berarti dalam sistem internasional adalah pemerintah dari negara kebangsaan, padahal banyak pelaku individu yang mampu membuat kehadiran mereka lebih terasa dalam hubungan-hubungan internasional. Hubungan-hubungan itu sebenarnya dapat dilakukan dengan melahirkan undang-undang yang berpihak pada kepentingan nasional. Paling tidak Cina dapat dijadikan contoh, demikian menurut Candra Irawan 202 telah menyesuaikan peraturan HKI-nya dengan memaksimalkan ketentuan UU HKI-nya Kata ”kepentingan nasional” menjadi kata kunci dalam penyusunan UU HKI di Negeri yang selama bertahun-tahun berseteru dengan Amerika. Ada lima kebijakan politik (hukum dan ekonomi) yang ditempuh Cina dalam menghadapi TRIPS Agreement : 202 Candra Irawan, Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 156-157. 285 Pertama, dalam undang-undang HKI-nya Cina membuat ketentuan-ketentuan pasal yang melindungi kepentingan nasionalnya. memberikan syarat kepada perusahaan Penanaman Modal Asing untuk melakukan investasi di Cina agar melakukan alih teknologi kepada perusahaan lokal, sebaliknya jika ternyata praktek PMA itu hanya semata-mata melakukan impor teknologi asing bukan alih teknologi maka perusahaan itu dimasukkan dalam daftar terlarang. memberikan toleransi terhadap tindakan pelanggaran HKI sepanjang dianggap mampu mendorong warga negara atau perusahaan lokal menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dari praktek pelanggaran HKI tersebut. tidak terburu-buru mengabsesi konvensi WTO/TRIPs Agreement. Cina baru resmi masuk anggota yang ke-143 pada bulan Desember 2001. Cina tidak pernah gentar terhadap tekanan asing. 203 Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima, Demikian pula India menjalankan politik hukum HKI-nya untuk kepentingan nasional negaranya dengan memuat ketentuanketentuan dalam peraturan perundang-undangan HKI-nya berupa klausule-klausule normatif yang secara tegas melindungi kepentingan negaranya. Misalnya saja ketentuan mengenai lisensi wajib dapat diterapkan terhadap paten yang tidak tersedia dalam masyarakat dengan harga yang wajar. Demikian pula dalam lapangan hukum hak cipta, apabila pemilik atau pemegang hak cipta menolak menerbitkan ulang suatu karya padahal kepentingan umum membutuhkan karya tersebut, lisensi wajib dapat dilaksanakan. Dengan alasan kepentingan nasional, Pemerintah India dapat memanfaatkan hak cipta atau pemegang hak cipta dengan membayar royalty yang wajar. Tentu saja batas kewajaran itu menurut perhitungan-perhitungan pemerintah India sendiri. Dalam bidang merek misalnya, apabila merek tersebut berpotensi untuk menyesatkan masyarakat atau menyinggung keyakinan agama, atau mengandung unsur pornografi merek tersebut tidak boleh didaftarkan. Dalam bidang desain industri, Pemerintah India dapat menolak pendaftaran apabila bertentangan dengan kepentingan umum atau moralitas. Demikian juga dalam bidang desain tata letak sirkuit terpadu, apabila mengganggu kepentingan pertahanan dan keamanan India hak tersebut ditolak untuk didaftarkan. Demikian seterusnya, Pemerintah Hindia-pun memanfaatkan waktu tenggang yang diberikan oleh WTO untuk mempersiapkan diri memperkuat sistem pengembangan HKI-nya sebelum tanggal 1 Januari 2005. India juga terus memperkuat negosiasi dan kritis terhadap negara-negara maju yang melakukan tekanan terhadap negerinya. India sangat terkenal dan 203 Ibid, hal. 159-162. 286 ketat dalam mengamankan asset dan hak kekayaan intelektual nasionalnya. Bagi India, negara majulah yang selama ini memanfaatkan sumber daya genetik (hayati) yang banyak dihasilkan oleh negaranegara berkembang. Dapat difahami bahwa, setelah mencermati politik Hukum HKI Cina dan India, mengapa masyarakat Indonesia kemudian menjadi tidak patuh terhadap undang-undang Hak Cipta Nasionalnya sendiri, itu dikarenakan undang-undang Hak Cipta Nasional yang disusun tidak aspiratif, tidak direncanakan sedemikian rupa dengan baik guna melindungi kepentingan nasional serta tidak mengacu pada konsep wawasan politik Pembangunan Hukum Nasional yang dituangakan dalam dokumen resmi negara sebagai dokumen Politik Pembangunam Hukum Nasional. Namun demikian tidaklah berarti Undang-undang hak cipta Indonesia hari ini kering sama sekali dari nilai kebangsaan. Paling tidak terdapat 7 pasal dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002 yang secara normatif berpangkal pada nilai-nilai kebangsaan. 204 Akan tetapi sekalipun nilai-nilai kebangsaan itu telah diadopsi dengan baik dalam Undang-undang Hak Cipta Nasional, masih juga terdapat penolakan masyarakat terhadap ketentuan normatif yang termuat dalam undang-undang itu. Sikap penolakan atau perlawanan terhadap norma hukum haruslah dipahami dari berbagai aspek. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidak patuhan masyarakat terhadap hukum selalu diawali dari norma hukumnya sendiri yang tidak memberikan suasana nyaman kepada anggota masyarakat. Ketidak patuhan terhadap norma hukum juga dipicu oleh suatu keadaan yang memaksa atau keadaan yang membuat anggota masyarakat tidak mempunyai pilihan. Membeli hasil karya sinematografi bajakan yang harganya lebih murah atau membeli hasil karya sinematografi yang original yang harganya lebih mahal adalah sebuah pilihan keputusan yang tidak hanya didasarkan kepada pertimbangan moral tetapi juga pertimbangan ekonomi. Dalam masyarakat yang semakin hari semakin sarat dengan pandangan hidup 204 Pasal 10, Negara pemegang hak cipta atas ciptaan atau karya atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional, hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat, pasal 11 atas ciptaan yang tidak diketahui siapa penciptanya. Pasal 17, pengumuman ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah, Pasal 18, pengumuman suatu ciptaan yang diselenggaraan oleh Pemerintah untuk kepentingan nasional, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak cipta dan kepadanya diberikan imbalan yang layak (lisesnsi wajib), Pasal 22 untuk kepentingan keamanan dan untuk keperluan proses peradilan pidana, hak cipta atas potret dapat diumumkan atau diperbanyak. Pasal 31, Batas waktu ciptaan atas hak cipta yang dipegang atau dilaksanakan oleh negara.Pasal 47, perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia. 287 materialis atau kebendaan dengan hitungan-hitungan ekonomis pastilah akan memilih langkah-langkah yang pragmatis, menguntungkan, yang akhirnya menjatuhkan pilihannya dengan membeli karya sinematografi hasil bajakan. Terjadi sebuah pergeseran dari sikap patuh atau protogonis menjadi sikap antagonis yang dalam banyak kasus di Republik ini menjadi pilihan perilaku dalam menyikapi berbagai keadaan yang tercipta sebagai akibat pengelolaan pemerintah yang tidak konsisten dengan pilihan politik hukumnya yang bersumber dari nilai-nilai Ketuhanan yang terpatri dalam ideologi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. 205 Sikap ketidak patuhan, pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. Pilihan pragmatis, substansi hukum yang jauh dari nilai religius, penegakan hukum hak cipta yang tidak konsisten adalah merupakan sederetan gambaran dari kegagalan undang-undang hak cipta nasional dalam meresepsi nilai-nilai Ketuhanan dalam undang-undang hak cipta nasinalnya namun disisi lain memperlihatkan keberhasilannya dalam praktek transplantasi hukum asing yang bersumber dari pandanganpandangan sekuler, kapitalis dan liberal. Banyak catatan yang terjadi yang dapat diungkap beberapa tahun belakangan ini tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi baik pada tingkat regional maupun tingkal global yang dilakukan oleh kelompok205 Perilaku antagonis itu tidak hanya terjadi karena penolakan terhadap norma hukum, tetapi juga terjadi karena sikap aparat penegak hukum. Masih jelas diingatan kita tentang pertikaian berdarah antara Satpol PP dengan warga di daerah Jakarta Utara. Kekerasan yang memakan korban aparat dan warga kembali jadi pilihan saat sekitar 2.000 polisi pamong praja mencoba menggusur kompleks makam Mbah Priok, di Jakarta Utara. Permasalahan ini seharusnya bisa diselesaikan dengan “kepala dingin”. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya Tindakan represif ditunjukan oleh kedua belah pihak ini mengakibatkan jatuhnya tiga orang korban jiwa di pihak Satpol PP. Sehari sebelumnya kerusuhan juga pecah saat Satpol PP Kota Tangerang menggusur pemukiman warga Cina Benteng, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh Satpol PP merupakan sebuah tragedi yang patut kita sayangkan. Bagaimana tidak, tragedi tersebut dilakukan oleh pihak yang paling berkuasa, yaitu negara. Inilah yang menghasilkan apa yang disebut sebagai kekerasan struktural, yaitu kekerasan yang digunakan oleh struktur kekuasaan yang dapat berupa aparat, tentara, pemerintah, dan atau birokrasi. Peradaban moderen memang secara de jure dan de facto memberi wewenang kepada negara sebagai satu-satunya institusi yang memiliki legitimasi melakukan kekerasan. Padahal kekerasan adalah tetap kekerasan yang memiliki unsur pemaksaan, destruksi, dan pengingkaran sebagian atau seluruh kebebasan, dan tidak menjadi soal siapa pelakunya. Bentuk-bentuk kekerasan ini antara lain, beating, (arbritrarily) killing, illegal detention, robbing, (systematic) raping, assaults on civilian, forced relocation, torturing, indiscriminate use of weapon, isolation, stigmatization, blocking acces, dan election fraud. Apa yang dilakukan oleh Satpol PP di dua contoh kasus diatas bisa dikategorikan penggunaan kekerasan kepada masyarakat sipil (assaults on civilian), dan relokasi secara paksa (forced relocation). 288 kelompok kecil yang tidak bertanggungjawab kepada siapapun kecuali pada diri mereka sendiri. Kasus-kasus terorisme penyeludupan senjata, obat-obatan terlarang yang beroperasi di pinggir sistem kenegaraan adalah wujud dari reaksi terhadap kompleksitas yang direduksi dari sistem internasional yang bias. Massa yang tak terorganisir yang tanpa sadar bertindak secara serentak juga memberikan dampak yang sama besarnya pada gangguan terhadap stabilitas dan keamanan dalam satu negara yang berujung pada ketidak stabilan politik dan kegoncangan pada ekonomi. Keadaan ini pada gilirannya akan melemahkan posisi negara yang mengundang kekuatan imperialisme terselubung. Untuk mengantisipasi itu, meminjam gagasan Galtung negara-negara dunia ketiga harus membangun “kekuatan dari dalam” sebagai pengakuan bahwa ketidak stabilan, konflik, kemiskinan hanya membuka peluang kepada negara-negara maju untuk melakukan intervensi untuk tidak dikatakan sebagai penjajahan dalam bentuk imperalisme terselubung. 206 E. Perubahan dan Pergeseran Nilai Musyawarah dan Mufakat Tak mudah memang mewujudkan cita-cita negara yang selalu dirumuskan secara garis lurus (linear) dan berkepastian (deterministic) yang berlandaskan pada satu idealisme. Apalagi dengan menggunakan satu sudut pandang tunggal dengan satu disiplin tertentu, yang didorong oleh keinginan kuat untuk menghasilkan sebuah “universal model”.207 206 Johan Galtung, There Art Alternatif Four Road to Peace and Security, Spokesman Press, Nothingham, 1984 dalam Soedjatmoko, Ibid, hal. 155. 207 Inilah sumber dari kemunculan macam-macam proyeksi dewasa ini : proyeksi pertumbuhan ekonomi (economic development), bahkan prognose tentang transformasi kebudayaan, proyeksi pertumbuhan masyarakat (social change ; social transformation), proyeksi perkembangan politik (political development) dan lainnya. Semua itu kemudian menghasilkan semacam gambaran-gambaran “unilinear deterministic continuous change” yang bersifat “stylistic” atau “idealistic” dan yang diangkat dari kenyataan-kenyataan yang serba tidak rapi itu. Yang hebat : semua prakiraan-prakiraan tampak seperti membawa kita semua ke “sebuah tujuan” atau “end situation”, yang dinyatakan sebagai misalnya “masyarakat modern”, ekonomi industrialisasi” atau “open-market democracy”, yang juga anehnya semua seperti menuju ke sebuah gambaran situasi yang homogeny serupa yang kita jumpai di masyarakat Peradaban Barat. Hegemoni global dari peradaban tersebut yang berlangsung sejak Revolusi industri pada abad ke-18 di Inggris memang telah mencuatkan masyarakat peradaban itu tak ubahnya sebagai sebuah “utopia” – sebuah situasi yang diidamidamkan oleh masyarakat Barat dan elite di masyarakat negara-negara berkembang sebagai yang akan dituju oleh semua masyarakat di dunia, apapun latar belakang kebudayaannya, agamanya, sistem politiknya ataupun ideologinya, dan berapa lamanya pun proses yang mesti dijalani. Lebih lanjut lihat Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, 289 Model pembangunan hukumpun dirumuskan secara universal dan berlaku dalam satu kesatuan negara, hukum tunggal yang berlaku secara unifikasi di negeri yang sangat plural. Undang-undang hak cipta nasional untuk pertama kalinya disahkan, yakni Undang-undang No. 6 Tahun 1982 menggantikan wet produk Kolonial Belanda yakni Auteurswet 1912 Stb. No. 600, undang-undang ini dimaksudkan berlaku secara unifikasi. Secara filosofis-ideologis, undang-undang yang baik haruslah dapat menampung semua aspirasi masyarakat. Oleh karena itu politik hukum legislasi nasional harus diarahkan untuk mencapai tujuan yakni menyahuti cita-cita negara antara lain mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dalam sebuah negara yang luas dengan penduduk yang relatif besar, undang-undang sebaiknya dirumuskan secara fleksibel sehingga diharapkan mampu mengikuti dan menyahuti aspirasi rakyat pada saat ia diterapkan. Cita-cita negara yang digagas oleh para pendiri bangsa yang secara abstrak telah dirumuskan dalam Pancasila sebagai landasan ideologi negara. Namun dalam perjalannnya sering kali para pemimpin lalai dalam mengejawantahkan landasan ideologi itu dalam produk peraturan perundang-undangan. Majelis Permusyawaratan Rakyat, misalnya (yang dulu dalam terminologi UUD 1945 sebelum diamandemen keanggotaannya adalah terdiri dari anggota DPR ditambah dengan utusan golongan) yang memiliki kedudukan tertinggi dalam kebijakan legislasi, dari waktu ke waktu memperlihatkan kinerja yang tidak mengacu pada cita-cita negara Indonesia merdeka, seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Bung Karno. Kepemimpinan Bung Karno lebih memprioritaskan pada pembangunan dalam bidang politik. 208 Menerawang Indonesia Pada Dasawarsa Ketiga Abad ke-21, Alvabet, Jakarta, 2012, hal. 6-7. 208 Pembangunan dalam lapangan kebudayaan-pun diarahkan kepada kebutuhan politik meskipun secara tegas dalam TAP MPRS No. II Tahun 1960 ditegaskan agar warga negara Indonesia mengukuhkan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia dengan menolak pengaruh-pengaruh buruk dari kebudayaan asing. Pancasila masih dijadikan landasan manifesto politik Republik Indonesia. Perekonomian-pun masih didasarkan pada kepentingan-kepentingan politik. Singkat kata, Bung Karno ingin mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin politik bangsa Indonesia sampai akhir kejatuhannya di penghujung tahun 1966. Padahal periode 1945-1966 itu adalah periodesasi yang didalam babakan sejarah keberlakuan undang-undang hak cipta nasional yang berasal dari hukum Kolonial. Bung Karno dalam orasinya selalu mengumandangkan dan memperlihatkan kebenciannya terhadap kapitalis. Tetapi ia tetap saja membiarkan berlakunya undang-undang yang bernuansa kapitalis. Bung Karno juga dalam berbagai orasinya menentang ideologi Barat tapi ia tetap saja membiarkan berlakunya hukum-hukum di wilayah Indonesia merdeka berasal dari hukum Barat. 290 Kebijakan legislasi nasional dalam bidang perlindungan hak cipta (tentu saja tidak terkecuali di bidang-bidang lainnya) tidak pernah direspon dengan baik oleh kalangan legislatif sampai berakhirnya masa kepemimpinan Bung Karno. Era kepemimpinan Soeharto, politik legislasi nasional juga menjadi retorika yang sulit untuk dipahami dalam perspektif negara hukum. Produk legislatif memanglah mulai terlihat lebih banyak dilahirkan pada masa kepemimpinan Soeharto. Akan tetapi produk legislatif lebih banyak menyahuti keinginankeinginan pemerintah (eksekutif). Sejak dikukuhkannya Soeharto menjadi presiden di awal tahun 1967, baru pada tahun 1982 atau tepatnya 15 tahun kemudian barulah undang-undang hak cipta peninggalan Kolonial Belanda digantikan dengan undang-undang hak cipta nasional meskipun Undang-undang No. 6 Tahun 1982 ini menyisakan banyak perdebatan karena undangundang ini masih sebagian besar mengacu pada roh atau spirit atau ideologi kapitalis yang bersumber dari hukum Barat. 209 Memang hukum peninggalan Kolonial Belanda tidaklah terlalu buruk untuk diteruskan di dalam negeri Indonesia merdeka, asal saja politik legislasi atau kebijakan pembangunan hukum nasional dapat menyaring norma-norma konkrit yang ada dalam undang-undang peninggalan Kolonial Belanda itu dengan ideologi Pancasila. Disaring dengan menggunakan ukuran-ukuran nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Disaring dengan menggunakan The Original Paradicmatic Values of Indonesia Culture and Society, tentu saja pekerjaan demikian itu bukanlah pekerjaan yang mudah untuk dilakukan. Meskipun pada periode pemerintahan Soeharto telah terjadi perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1982 dengan Undangundang No. 7 Tahun 1987 itupun tidak bermakna bahwa Undangundang No. 7 Tahun 1987 itu telah menyahuti aspirasi rakyat. Adalah desakan pemerintah Amerika agar Indonesia segera merobah Undangundang No. 6 Tahun 1982 yang tidak aspiratif dengan keinginan Amerika dan negara-negara maju. Kehadiran Presiden Amerika di Bali bertemu dengan Presiden Soeharto menimbulkan spekulasi di kalangan akademis khususnya akademisi bidang hukum bahwa pembicaraan 209 Auteurswet 1912 Stb. No. 600 adalah undang-undang hak cipta yang diberlakukan di Negeri Belanda. Wet ini disempurnakan oleh Kerajaan Belanda dalam rangka menyahuti keinginan masyarakat Eropa yang ketika itu sebahagian besar telah meratifikasi dan menjadi anggota Konvensi Bern tahun 1881. Auteurswet 1912 ini menggantikan Undang-undang Hak Cipta Kerajaan Belanda sebelumnya. 291 empat mata antara Presiden Amerika dengan Presiden Soeharto tidak lebih dari menancapkan keinginan Amerika untuk memproteksi hak cipta warga negara mereka. 210 Segera setelah kembali Presiden Amerika ke negerinya, Soeharto memerintahkan Menteri/Sekretaris Kabinet yang pada waktu itu dijabat oleh Moerdiono, dan Soeharto kemudian menerbitkan Keppres yang dikenal dengan Keppres 38 A yang isinya membentuk tim untuk menyusun penyempurnaan Undangundang No. 6 Tahun 1982. Sekali lagi, eksekutiflah yang lebih dominan dalam penyempurnaan Undang-undang No. 6 Tahun 1982. Setelah tim Keppres 38 A menyelesaikan tugas-tugasnya, maka hasil tim itu kemudian dirumuskan dan terbentuklah rancangan undangundang untuk perubahan Undang-undang No. 6 Tahun 1982. Legislatif kemudian bersidang dan tanpa pembahasan yang berlarut-larut karena memang demikianlah kehendak atau keinginan pemerintah (tentu saja dengan menyahuti keinginan pihak Amerika) akhirnya disahkanlah Undang-undang No. 7 Tahun 1987 yang isinya adalah menyempurnakan dari bahagian-bahagian pasal-pasal Undang-undang No. 6 Tahun 1982. Legislatif hanya bekerja di penghujung menjelang kelahiran Undang-undang No. 7 Tahun 1987. Selebihnya yang bekerja lebih awal adalah para eksekutif di bawah komando menteri Seketaris Kabinet pada masa pemerintahan Soeharto. Masih dalam orde Pemerintahan Soeharto, pada tahun 1997 hal yang sama seperti yang terjadi pada masa-masa sebelumnya terulang kembali. Pasca ratifikasi GATT 1994/WTO, Indonesia dihadapkan pada satu keharusan untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan bidang hak kekayaan intelektualnya dengan tuntutan GATT 1994/WTO yang salah satu instrumen di dalamnya memuat TRIPs Agreement. Mujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, akhirnya rezim Soeharto dihadapkan kembali pada penyempurnaan Undang-undang No. 7 Tahun 1987 melalui Undangundang No. 12 Tahun 1997. Terkesan bahwa Undang-undang No. 12 Tahun 1997 ini dibuat secara terburu-buru. Ini adalah kebiasaan legislatif di negeri ini yakni membuat undang-undang sebagai 210 Terlepas dari Indonesia harus melindungi kepentingan warga negara asing terlebih-lebih melindungi kepentingan hak-hak kekayaan intelektual mereka akan tetapi kehadiran Ronald Reagen di Bali diawali dari banyaknya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh masyarakat Indonsia khususnya dalam bidang software komputer dan pelanggaran karya cipta lagu milik warga negara Amerika. Adalah lagu karya Bob Geldof yang khusus diciptakan untuk menghimpun dana bantuan kemanusiaan life aid atas bencana yang dihadapi masyarakat Afrika ketika itu akan tetapi lagu-lagu itu dibajak di Cina dan di Indonesia sehingga dana bantuan kemanusiaan itu menjadi tidak optimal. 292 pekerjaan borongan. Target pembuatan undang-undang telah disusun pada tiap-tiap tahun anggaran. Sinyalemen-sinyalemen pembuatan undang-undang ini dilakukan secara terburu-buru karena pada akhirnya Undang-undang No. 12 Tahun 1997 ini tidak juga dapat menyahuti secara keseluruhan keinginan-keinginan yang dikehendaki oleh TRIPs Agreement hasil Putaran GATT 1994/WTO, karena pada akhirnya undang-undang yang dibuat terakhir inipun harus juga mengalami penyempurnaan kembali melalui Undang-undang No. 19 Tahun 2002. Dominankah peranan legislatif pada penyusunan undangundang hak cipta nasional tersebut ? Uraian di atas memperlihatkan bahwa legislatif hampir dapat dipastikan tidak dominan dalam menyuarakan aspirasi dan kehendak rakyat dalam penyusunan undangundang hak cipta nasional tersebut. Situasi politik pada masa pemerintahan Bung Karno, dilanjutkan dengan pemerintahan Soeharto hampir tidak memberi ruang terhadap aspirasi dan suara rakyat yang disalurkan melalui lembaga legislatif. Karena pasca pemerintahan Soeharto, hiruk pikuk politik di negeri ini berkecambuk melebihi situasi politik pada pemerintahan sebelumnya. Kebebasan pers yang diikuti dengan keterbukaan di segala bidang yang juga didukung oleh kemajuan teknologi informasi secara bersamaan telah membuat pemerintah Indonesia pasca pemerintahan Presiden Soeharto menjadi lebih dinamis dan lebih banyak menimbulkan persoalan-persoalan baru yang sulit untuk ditemukan pada masa-masa pemerintahan sebelumnya. Namun di celah-celah kondisi politik dalam negeri yang demikian keikutsertaan Indonesia dalam keanggotaan GATT 1994/WTO tidak dapat diabaikan. Di celah-celah situasi itu tepatnya pada masa pemerintahan Megawati, Indonesia kembali dihadapkan pada penyempurnaan undang-undang hak cipta nasionalnya untuk disetarakan atau diselaraskan dengan TRIPs Agreement. Peranan lembaga legislatif juga hadir di saat-saat akhir pengesahan undangundang itu, karena pesan sesungguhnya telah lama diisyaratkan oleh TRIPs Agreement yakni pada saat ratifikasi GATT 1994/WTO pada tahun 1994. Dapat disimpulkan bahwa lembaga legislatif tidak lebih dari sebagai institusi untuk menjustifikasi agar undang-undang itu dapat diberlakukan secara sah di seluruh wilayah Republik Indonesia dan dapat pula diperlihatkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia telah memiliki undang-undang hak cipta dengan standard internasional. Peranan legislatif lagi-lagi telah bergeser dari yang seharusnya mempertahankan ideologi Pancasila kemudian memuat roh dari spirit yang terkandung dalam The Original Paradicmatic Values of Indonesia 293 Culture and Society untuk dijadikan penyaring dalam penyusunan undang-undang hak cipta nasional tak dapat lagi diwujudkan. Anggota legislatif sulit untuk dijadikan gantungan harapan masyarakat Indonesia dalam meluruskan ide, gagasan dan cita-cita pembangunan hukum nasional sebagai motor dalam roda kebijakan politik pembangunan hukum nasional. Tidak itu saja, dalam satu unit pekerjaanpun banyak ditemukan ketidak-kompakan. Sebagai contoh dalam Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, ditemukan hal-hal yang tidak perlu. (lihat pasal aturan peralihan dan rentang pendaftaran). Seharusnya pasal-pasal itu tidak diperlukan lagi, jika semua komponen yang ada pada saat undang-undang itu disusun berpikir secara sistemik. Jika sistem pendaftaran Hak Cipta menganut sistem dekleratif negatif, maka tidak perlu pasal yang memuat aturan tentang penghapusan pendaftaran hak cipta oleh suatu sebab atau oleh suatu keadaan. (vide pasal 44). Hapus atau tidak sebuah karya cipta dengan sistem pendaftaran dekleratif negatif tidak memberi dampak apa-apa kepada pencipta atau pemegang hak cipta dengan keberadaan pasal 44 Undangundang No. 19 Tahun 2002 itu. Demikian juga dengan ketentuan pasal 74 dan pasal 77. Pasal yang satu mengisyaratkan berlakunya ketentuan yang lama atau ketentuan yang ada sebelum undang-undang ini dilahirkan, pasal yang satunya lagi menegaskan tidak berlaku undangundang yang telah dibuat sebelumnya. Jika yang dimaksudkan oleh pasal 77 yang tidak berlaku adalah UU No.6 Tahun 1982, UU No.7 Tahun 1987 dan UU No.12 tahun 1997, maka itu berarti yang tidak berlaku adalah uu hak cipta yang pernah dibuat pada masa kemerdekaan. Bagaimana dengan nasib undang-undang hak cipta yang dibuat sebelum kemerdekaan yakni Auteurswet 1912 stb.No.600, apakah masih berlaku juga? Jika dirujuk pasal 74 Undang-undang No.19 Tahun 2002, jawabnya tetap masih berlaku. Sekuens nya sebagai berikut. Auteurswet 1912 stb.No.600 di bumi Indonesia diberlakukan dan mendapat tempat dalam wadah hukum di bumi Indonesia selama 70 tahun. Pemeberlakukan ini mengacu pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Pada waktu Undang-undang No. 6 Tahun 1982 disyahkan berlakunya di Indonesia, Auteurswet 1912 Stb. No.600 dicabut, dengan demikian tak ada tempat bagi Auteurswet 1912 Stb.No.,600 di bumi Indonesia. Selanjutnya Undang-undang No.6 Tahun 1982 diubah dengan Undang-undang No.7 Tahun 1987 dan Undang-undang No 12 tahun 1997. Ketiga undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1997. Ketika ketiga undang-undang itu dicabut di dalamnya ikut dicabut ketentuan yang 294 menyatakan mencabut Auteurswet Stb. 1912 No. 600, yang bermakna bahwa Auteurswet Stb. 1912 No.600 akan hidup dan berlaku kembali berdasarkan Pasal peralihan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dikuatkan oleh pasal 74 Undang-undang No.19 Tahun 2002. Pertanyaan adalah apakah memang begitu maksud pembuat undang-undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002. Jika demikian halnya wawasan politik hukum apa yang menjadi dadar pilihan politik hukum semacam itu. Di negeri asalnya Belanda saja pun, wet itu sudah tidak diberlakukan lagi, tapi justeru di Indonesia yang telah berkali-kali merubah, merevisi, mengganti dan bahkan menyesuaikan undangundang hak cipta nasiona nya dengan TRIPs Agreement dan pada satu masa pernah menegaskan telah mencabut wet itu, justeru dalam undang-undangnya yang terakhir menghidupkan dan memberlakukannya kembali. Ini adalah sebuah pandangan kritis, dari bahayanya menyusun undang-undang tidak berpikir secara sistemik. Seorang yang ahli hukum pidana merasa tak perlu memahami tentang hukum perdata. Seorang yang telah mengukuhkan keahliannya di bidang hukum Tata negara merasa tak perlu memahami hukum Acara Perdata atau Hukum Acara Pidana. Seorang yang merasa ahli hukum perdata, mengajukan banyak garis dan batasan dengan hukum dagang, hukum pasar modal, hukum perburuhan, hukum agraria dan lain sebagainya. Pandangan dan anggapan semacam ini, tidak saja membuat kering atau mengkerdilkan studi ilmu hukum tapi justeru menimbulkan kesenjangan dalam merumuskan wawasan politik hukum nasional. Memang dalam pengajaran keilmuan dalam bidang hukum, diharuskan untuk menjurus kepada spesialisasi pembidangan secara linier, agar publik dapat mengetahui bidang keahlian masing-masing, namun itu tidak berarti bahwa para ilmuwan hukum boleh melepaskan pandangan dan kajiannya secara sistemik. Ini yang oleh Mariam Darus, Mahadi dan terakhir M.Solly Lubis kukuhkan sebagai pendekatan sistem dalam kajian Ilmu hukum. Sistem hukum yang memuat asas-asas hukum dan norma hukum. Sistem hukum yang berisikan substasi, struktur dan kultur hukum, menurut pandangan Friedman. Kritik tajam yang mesti diungkapkan dalam disertasi ini adalah tidak ditempatkannya dengan baik, hukum (Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002) hak cipta nasional dalam sistem hukum Perdata. Pemahaman terhadap hukum perdata mengacu pada dua konsep hukum. Pertama menurut konsep atau pandangan ilmu pengetahuan. Bahwa hukum perdata menurut pandangan ilmu pengetahuan terdiri dari dari hukum orang 295 (personenrecht), hukum keluarga (familierecht), hukum harta kekayaan (vermogensrecht) dan hukum kewarisan (erfecht). 211 Kosep kedua, mengacu pada pandangan menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata, yaitu Hukum Tentang orang, Hukum Tentang benda, hukum tentang Perikatan dan Hukum Tentang Daluwarsa. Hukum tentang Daluwarsa kemudian tak dapat dimasukkan dalam cakupan hukum perdata materil, karena daluwarsa itu adalah lebih tepat diposisikan sebagai hukum acara atau hukum formil sebab mengandung isi tentang tatacara mendapatkan hak dengan lampaunya waktu. Pemusatan pemikiran yang utama untuk menempatkan Hak Cipta sebagai bahagian dari sistem hukum perdata haruslah dilihat terlebihg dahulu karakteristik atau ciri-ciri hak cipta itu. Berikut ini dapat dinukilkan tentang ciri-ciri hak cipta sebagai berikut: 1. Hak cipta itu dihasilkan oleh daya cipta, rasa dan karsa manusia, perorangan atau kelompok. 2. Mempunyai nilai ekonomis. 3. Tidak terlihat dalam arti tidak berwujud (immateril) 4. Boleh dialihkan melalui, pewarisan., hibah, wasiat,perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan oleh unang-undang (termasuk jual beli, penyewaan, lisensi,dan lain-lain, vide pasal 3). 5. Dianggap sebagai benda bergerak (ditentukan oleh undang-undang bukan karena sifatnya, vide pasal 3). 6. Hak untuk mengumumkan atau memperbanyak karya cipta 7. Adanya hak moral 8. Mengenalsistem pendaftaran meskipun dekleratif negatif 9. Dapat dipertahankan terhadap siapa saja yang melanggar hak tersebut, baik secara perdata,pidana maupun secara administrasi 10. Jangka waktu kepemilikan selama hidup pencipta sampai 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia, untuk jenis karya cipta lain dibatasi secara bervariasi. Berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik hak cipta tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak cipta itu adalah benda, yakni benda immateril, benda tidak berwujud, dapat menjadi obyek harta kekayaan dan dapat dijadikan obyek jual beli, obyek pewarisan, hibah, wasiat, jual beli, lisensi atau sewa menyewa. Sama dengan perolehan atau 211 Lebih lanjut lihat Mariam Darus Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Alumni, Bandung, 2010, hal. 4. 296 penguasaan terhadap benda materil, maka untuk mendapatkan karya ciptapun seseorang harus mengeluarkan, biaya, tenaga dan bahkan waktu yang tidak sedikit. Itulah sebabnya hak pencipta dalam kerangka hukum disebutkan sebagai pihak yang paling berhak atau disebut sebagai pemegang hak eksklusif atau hak khusus, karena ia diciptakan atas kemampuan yang bersifat khusus pula. Tak dapat dillakukan oleh semua orang yang tidak memiliki keahlian atau talenta yang khusus melekat pada dirinya. Para pelukis, komposer, penyanyi, para aktor (pelakon), para penari, para pengarang, peneliti dan penulis mestilah dibekali keahlian dan talenta khusus untuk itu. Eksklusif itulah frase yang tepat untuk menyebutkan hak yang dimiliki oleh para pencipta. Karena itu pula pada hasil karya cipta, meskipun hakya telah berakhir, hak moral tetap harus dilekatkan. Nama pencipta harus tetap dilekatkan pada hasil karya cipta itu. Kembali kepada perlunya pemahaman sistemik dengan menempatkan hak cipta sebagai hukum benda dan bahagian dari hukum perdata, membawa konsekuensi logis, bahwa asas-asas hukum perdata atau prinsip-prinsip pokok hukum benda akan melekat dan tak menjadi rujukan dalam poenyusunan undang-undang hak cipta nasional. Secara makro (dalam kerangka sistem nasional yang luas, meliputi ipoleksosbud) langkah-langkah yang harus dipenuhi dalam penyusunan undang undang adalah didahului oleh pemahaman ideologis, kemudian juridis terakhir pemahaman politis,sebagai tiga landasan ketatanegaraan dengan pendekatan sistem. Kebijakan strategis (politik hukum) penyusunan uu hak cipta nasional haruslah mengacu pada tiga landasan ketatata negaraan, sebagaimana secara terus menerus dikumandangkan oleh M.Solly Lubis dalam berbagai ruang seminar dan ruang kuliah kemudian dituangkan dalam berbagai buku yang dapat dijadikan rujukan ilmiah akademik. 212. Secara mikro (dalam kerangka sistem nasional yang sempit yakni sistem hukum) pendekatan Mahadi dan 212 Lebih lanjut lihat M. Solly Lubis, Serba-Serbi Politik & Hukum, PT. Sofmedia, Jakarta, 2011, lihat juga M. Solly Lubis, Landasan dan Teknik Perundangundangan, Mandar Maju, Bandung, 1995, Lihat juga M. Solly Lubis, Pembahasan UUD 1945, Alumni, Bandung, 1997, lihat juga M. Solly Lubis, SH, Prof. DR, Reformasi Politik Hukum : Syarat Mutlak Penegakan Hukum Yang Paradigmatik, Orasi Ilmiah Dalam Rangka Ulang Tahun ke-80 Prof. DR. M. Solly Lubis, SH, Guru Besar Emeritus, Februari 2010, juga lihat M. Solly Lubis, SH, Prof. DR. Hukum Tatanegara, Mandar Maju, Bandung, 2008 , lihat juga M. Solly Lubis, SH, Prof. DR., Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, Mandar Maju, Bandung, 2009, Lihat juga M. Solly Lubis, SH, Prof. DR, Paradigma Kebijakan Hukum Pasca Reformasi, Dalam Rangka Ultah ke-80 Prof. Solly Lubis, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010. Lihat juga M. Solly Lubis, SH, Prof. DR, Sistem Nasional, Mandar Maju, Bandung, 2002. 297 Mariam Darus, dapat dirujuk untuk memposisikan Hak Cipta dalam kerangka sistem hukum perdata bidang hukum benda. Dengan menemukan karakteristik dan asas-asas yang tersembunyi dalam hak cipta tersebut dan ini akan memperjelas kedudukan hak cipta dalam lapangan hukum perdata yakni merupakan sub sistem hukum benda. Meminjam kerangka analisis sistem yang dikembangkan oleh tiga begawan hukum asal Fakultas Hukum Universitas Sumatera utara tersebut maka, kritik yang dapat diajukan dalam undang-undang hasil produk terakhir lembaga legislatif nasional yang membuahkan Undangundang No. 19 Tahun 2002 hasil transplantasi hukum asing ini adalah : 1. Pasal 3 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 yang memuat ketentuan tentang hak cipta sebagai benda bergerak sebaiknya dihapus saja, tidak ada juga guna atau fungsinya, lebih baik menyebutkan bahwa hak cipta adalah benda immateril, atau haka kekayaan intelektual sebagai benda tidak berwujud. Pembuat undang-undang sebaiknya memahami konsekkuensi hukum dari klasifikasi benda bergerak dengan benda tidak bergerak. Klasifikasi itu berhubungan erat dengan pengalihan, levering, atau pada saat ia dijadikan obyek jaminan. Pada peristiwa penempatan hak cipta sebagai benda bergerak dalam undang-undang hak cipta nasional hampir tidak ditemukan kegunaan atau kemanfaatannya. 213 213 Pengelompokan benda ke dalam kelompok benda bergerak dan benda tidak bergerak menurut Sri Soedewi, mempunyai arti penting dalam hal bezit levering dan beswaring. Lebih lanjut lihat, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata, Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal. 22. Dalam konteks ini jika pandangan Sri Soedewi dihubungkan dengan pandangan Volmar yang menyatakan bahwa untuk penyerahan benda bergerak dapat dilakukan secara nyata sedangkan untuk benda tidak bergerak, penyerahannya dilakukan dengan pendaftaran dengan menggunakan akte autentik. Lebih lanjut lihat H.F.A., Volmar, terjemahan IS. Adiwimarta, Pengantar Studi Hukum Perdata (I), Rajawali Pers, Jakarta, 1983, hal. 195. Hak cipta tidak dapat dilakukan dengan penyerahan nyata karena ia mempunyai sifat yang manunggal dengan penciptanya dan bersifat tidak berwujud. Hak ciptapun tidak dapat digadaikan karena jika digadaikan itu berarti si pencipta harus ikut pula beralih ke tangan si kreditur. Oleh karena pengalihan hak cipta hanya dapat dilakukan dengan sebuah akte dan dapat juga didaftarkan agar ia bersifat autentik, maka sebenarnya lebih tepat jika hak cipta ini digolongkan sebagai benda terdaftar. Jika hari ini sistem pendaftaran hak cipta masih menganut sistem pendaftaran deklaratif negatif, maka sebaiknya tak perlulah diberi ketegasan didalam satu pasal undang-undang bahwa hak cipta ini termasuk dalam kelompok benda bergerak oleh karena dari segi kegunaannya hampir tidak memperlihatkan manfaat sama sekali. Lebih lanjut lihat OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 66. 298 2. Ketentuan pasal 74 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 sebaiknya dihapuskan, karena sudah tidak relevan lagi dan itu membuka ruang untuk diberlakukannya Auteurswet Stb 1912 No.600 yang menimbulkan konflik hukum dalam penerapannya. 3. Pemerintah tidak mengambil porsi yang berlebihan dalam undangundang ini untuk memposisikan diri sebagai institusi pemebuat peraturan (meskipun peraturan oreganik). 4. Negara tidak diperkenankan memposisikan dirinya sebagai owner, cukup sebagai subyek yang memgang hak menguasai oleh negara. Kritik semacam ini seharusnya tidak lagi muncul jika penyelenggara negara dan pemerintahan di republik ini berfikir dengan paradigma sistem yang dapat menghilangkan kecongkakan sektoral. Kritik terakhir yang juga harus dikemukakan dalam disertasi ini adalah penempatan hukum, bidang hak cipta menurut versi Suyud Margono. Dalam tulisannya halaman 83 membuat skema tentang perkembangan sistematika hak cipta dalam sistem hukum perdata sebagai berikut : Skema : 8 Perkembangan Sistematika Hak Cipta Dalam Sistem Hukum Perdata HUKUM PERDATA Hukum Harta Pribadi Hukum Harta Kekayaan Hukum Keluarga Hukum Waris Hukum Benda Hukum Perikatan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) : 1. Hak Cipta 2. Hak Milik Industri a. Merek b. Paten c. Desain Industri d. Rahasia Dagang e. Sirkuit Terpadu f. Varietas Tanaman Dalam skema di atas, Suyud Margono menempatkan hukum benda sejajar dengan hukum hak kekayaan intelektual yang merupakan sub sistem dari hukum harta kekayaan yang berada dalam sistem hukum 299 perdata. Kritik yang diajukan adalah mensejajarkan hukum benda dengan hukum hak kekayaan intelektual bersama-sama dengan hukum perikatan adalah penempatan yang tidak mengacu pada pola pikir sistem hukum. Jika mengacu pada pembahagian hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum 214 maka hukum harta kekayaan itu terdiri dari dua bahagian yaitu hukum benda dan hukum perikatan. Itulah sebabnya kemudian Kitab Undang-undang Hukum Perdata menempatkan hukum benda pada bab sendiri dan hukum perikatan pada bab yang tersendiri pula. Tapi keduanya termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan. Bagaimana dengan kedudukan hukum hak kekayaan intelektual ? Hukum hak kekayaan intelektual sebenarnya bahagian dari hukum benda atau sub sistem hukum benda yang merupakan bagian hukum harta kekayaan yang berada di dalam sistem hukum perdata. Sehingga tidak tepat jika hukum benda disejajarkan dengan hukum hak kekayaan intelektual sebagaimana dikemukakan oleh Suyud Margono dalam tulisannya tersebut di atas. Jika hendak disempurnakan maka skemanya adalah sebagai berikut : 214 Lihat lebih lanjut Suyud Margono, Hukum Hak Cipta Indonesia Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)-TRIPs Agreement, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010. 300 Skema : 9 Kedudukan Hak Cipta Dalam Sistem Hukum Perdata HUKUM PERDATA Hukum Harta Pribadi Hukum Harta Kekayaan Hukum Benda Benda Materil Hukum Keluarga Hukum Waris Hukum Perikatan Benda Immateril Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) : 1. Hak Cipta 2. Hak Milik Industri a. Merek b. Paten c. Desain Industri d. Sirkuit Terpadu e. Varietas Tanaman Dalam skema di atas, menjadi terang dan jelas kedudukan hak cipta sebagai hak atas benda immateril. Karena itu juga harus dihapuskan atau dihilangkan rahasia dagang sebagai bahagian dari hak kekayaan intelektual. Alasannya adalah karena tidak ada hak kebendaan yang dihasilkan dalam rahasia dagang tersebut. Rahasia dagang dalam prakteknya adalah sebuah temuan atau invensi yang dirahasiakan oleh penemunya. Jadi rahasia dagang adalah merupakan paten yang dirahasiakan. Bisa saja yang dirahasiakan itu tentang komposisi obatobatan, teknik dan cara pembuatannya. Bisa juga yang dirahasiakan itu komposisi dari jenis makanan yang dirahasiakan cara memasak dan mengolahnya. Jadi rahasia dagang bukan suatu benda immateril 301 melainkan sebuah temuan benda imateril yang dirahasiakan. Itulah sebabnya menurut pandangan kami rahasia dagang (termasuk juga unfair competition atau persaingan curang) tidak semestinya ditempatkan kedalam sub sistem hukum benda immateril yang bersama-sama berada dalam sistem hukum perdata nasional. Kekeliruan di atas perlu dikritik karena ini terjadi atas suatu pandangan yang tidak sistemik dalam melihat obyek hukum (benda) dalam satu sistem hukum yang menaunginya. Kekeliruan ini terjadi lebih dikarenakan karena pandangan yang sempit dan linier yang membatasi analisis dengan dinding-dinding keahlian tertentu dengan ego disiplin ilmu tertentu. Sudah saatnya dibuka pandangan yang seluas-luasnya untuk memposisikan hukum nasional melalui perspektif sejarah hukum dan politik hukum. Menempatkan hukum hak cipta dalam bahagian hukum harta kekayaan yang merupakan sub sistem dari hukum benda bukan tidak beralasan, sebab manakala norma-norma hukum konkrit yang dituangkan dalam undang-undang tidak cukup mampu memberikan jawaban dalam praktek penegakan hukum maka tugas untuk melakukan penemuan hukum harus dibuka seluas-luasnya. 215 Aktivitas penemuan hukum memang dapat dilakukan oleh siapa saja, akan tetapi hakim yang menjadi ujung tombak penemuan hukum jika norma hukum tidak cukup lengkap memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang dihadapi maka hakim harus kembali kepada asas hukum. Asas hukum menurut Mariam Darus dapat ditemukan dengan cara mengabstraksi norma hukum. Dengan metode abstraksi itu, maka ditemukanlah asasasas hukum yang tersembunyi di balik norma hukum. Mariam Darus menyebutkan bahwa asas hukum adalah merupakan sub sistem dalam sistem hukum. 216 215 Lihat lebih lanjut Sudikno Mertokusumo Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2009, Lihat juga Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan, UII Press, Yogyakarta, 2006. 216 Asas-asas hukum ini diperoleh melalui konstruksi yuridis yaitu dengan menganalisa (mengolah) data-data yang sifatnya nyata (konkrit) untuk kemudian mengambil sifat-sifatnya yang umum (kolektif) atau abstrak. Proses pencarian asas hukum ini disebut dengan mengabstraksi. Aturan-aturan hukum membentuk dirinya dalam suatu hukum itu dapat pula digolongkan dalam sub-sub sistem seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum ekonomi dan sebagainya. 216 Dengan demikian suatu sistem hukum didalam suatu negara dapat dibagi-bagi dalam bagianbagian (sub sistem hukum, sehingga antara hukum yang satu dengan hukum yang lain seharusnya saling berkaitan dan tidak boleh saling bertentangan oleh karena memiliki asas-asas dan sendi-sendi yang terpadu. Meskipun demikian, apabila terjadi pertentangan antara sub sistem hukum dapat diselesaikan melalui penggunaan asas-asas hukum. Lihat 302 Menempatkan hukum hak kekayaan intelektual dalam hukum benda konsekuensinya adalah jika norma hukum yang mengatur hak kekayaan intelektual tidak cukup lengkap memberikan jawaban atas persoalan hukum yang diperlukan maka asas-asas hukum benda dapat dipergunakan untuk memberikan penyelesaian dalam sengketa hukum yang sedang dihadapi oleh para pihak. Mahadi 217 menulis dengan mengutip C.W. Paton memberi batasan tentang asas hukum, yaitu : “A principle is the broad reason which lies at the base of a rule of law”. (Asas ialah suatu pikiran yang dirumuskan secara luas yang mendasari adanya suatu norma hukum). Mahadi selanjutnya menguraikan unsur-unsur menurut defenisi Paton sebagai berikut : 1. Alam pikiran 2. Rumusan luas 3. Dasar pembentukan norma hukum Jika suatu norma hukum telah terbentuk, dapat dipahami bahwa di balik pembentukan norma hukum itu terdapat dasar, dasarnya itulah yang dirumuskan sebagai asas yang dilator belakangi oleh alam pikiran pembuat undang-undang. Di Indonesia alam pikiran itu harus diuji dengan Pancasila sebagai landasan filosofis pembuatan undangundang. Pancasila itu adalah hasil abstraksi dari the original paradigmatic value of Indonesian culture and society 218 yang lebih lanjut Mariam Darus Badrulzaman, Hukum Benda Dalam Sistem Hukum Nasional Mariam Darus Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Alumni, Bandung, 2010. 217 Mahadi, Falsafah Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hal. 122. 218 Secara khusus, asas-asas yang terkandung dalam hukum benda dapat dilihat dari ciri-ciri hak kebendaan. Sri Soedewi menuliskan tentang cirri-ciri hak kebendaan dengan hak perorangan sebagai berikut : 1. Merupakan hak yang mutlak, dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. 2. Mempunyai zaaksgevolg atau droit de suite (hak yang mengikuti). Artinya hak it uterus mengikuti bendanya dimanapun juga (dalam tangan siapa pun juga) benda itu berada. Hak itu terus saja mengikuti orang yang mempunyainya. 3. Sistem yang dianut dalam hak kebendaan di mana terhadap yang lebih dahulu terjadi mempunyai kedudukan dan tingkat yang lebih tinggi dari pada yang terjadi kemudian. Misalnya, seorang eigenar menghipotikkan tanahnya, kemudian tanah tersebut juga diberikan kepada orang lain dengan hak memungut hasil, maka di sini hak hipotik itu masih ada pada tanah yang dibebani hak memungut hasil itu. Dan mempunyai derajat dan tingkat yang lebih tinggi dari pada hak memungut hasil yang baru terjadi kemudian. 4. Mempunyai sifat droit de preference (hak yang didahulukan) 5. Adanya apa yang dinamakan gugat kebendaan. 6. Kemungkinan untuk dapat memindahkan hak kebendaan itu dapat secara sepenuhnya dilakukan. Berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri hukum benda tersebut di atas, dapat ditarik asas-asas hukum sebagai berikut : 1. Asas absolutisme 2. Asas zaaksgevolg atau droit de suite 3. Asas prioritas kedudukan 4. Asas droit de preference 5. Asas perlindungan hak 6. Asas kesatuan atau keutuhan. Lihat lebih lanjut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Op.Cit, hal. 24. Disamping itu asas-asas umum yang berlaku dalam bidang hukum benda secara lebih rinci dikemukakan oleh Mariam 303 merupakan kumpulan dari tata nilai atau asas-asas hukum sebagai produk budaya yang abstrak. Asas-asas hukum benda tersebut dapat dirujuk baik dalam pembuatan norma hukum undang-undang hak cipta nasional maupun dalam penerapan. Asas hukum haruslah ditempatkan dalam sub sistem hukum. Dengan pendekatan sistem, semua persoalan hukum baik pada saat pembuatannya maupun pada saat penerapannya akan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Hukum kemudian dapat dirasakan sebagai sarana untuk mencapai keadilan, menciptakan kepastian hukum dan memberikan kemanfaatan. Hanya saja dalam proses perumusan kaedah hukum hak cipta nasional kelihatannya meninggalkan atau keluar dari sistem nasional sebagaimana dimaksudkan oleh M. Solly Lubis, dan mengingkari pendekatan sistem hukum sebagaimana pandangan Mahadi dan Mariam Darus. Keadaan ini berlangsung tidak terlepas dari suatu sebab yakni karena adanya pergeseran cara pandang yang seharusnya mengacu kepada cara pandang sistemik bergeser menjadi ego sektoral. Para anggota legislatif dalam banyak hal telah meninggalkan konsep demokrasi Pancasila yang meletakkan dasar musyawarah mufakat dan telah digantikan dengan konsep demokrasi liberal sehingga nilai-nilai musyawarah dan mufakat terutama dalam menentukan pasal yang berkaitan dengan sengketa perdata tidak sepenuhnya mengacu pada penyelesaian berdasarkan musyawarah dan mufakat akan tetapi diserahkan kepada lembaga peradilan formal seperti peradilan niaga, meskipun peluang untuk musyawarah dan mufakat itu telah dibuka juga melalui lembaga peradilan arbitrase seperti yang tertuang dalam Pasal 65 Undangundang No. 19 Tahun 2002. Akan tetapi untuk pelanggaran pidana Undang-undang No. 19 Tahun 2002 menetapkannya sebagai delik biasa sehingga peluang untuk penyelesaian melalui musyawarah dan mufakat itu menjadi tertutup. Oleh karena itu sudah seyogyanyalah sifat atau jenis delik pidana Undang-undang Hak Cipta ini harus dirobah menjadi delik aduan, bukan delik biasa. Darus : 1. Asas sistem tertutup 2. Asas hak mengikuti benda (zaaksgevolg, droit de suite) 3. Asas publisitas 4. Asas spesialitas 5. Asas totalitas 6. Asas accessie 7. Asas pemisahan horizontal 8. Asas dapat diserahkan 9. Asas perlindungan 10. Asas absolute (hukum pemaksa) Lebih lanjut lihat Mariam Darus Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Op.Cit, hal. 36-42. 304 F. Perubahan dan Pergeseran Nilai Ekonomi Pancasila Landasan filosofis pembentukan undang-undang hak cipta nasional mengacu pada landasan ideologi Pancasila sebagai grundnorm. Sebagai konsekuensinya maka, seharusnya undangundang hak cipta nasional akan mencerminkan muatan tata nilai sebagai asas-asas yang dituangkan dalam norma hukum (pasal demi pasal) undang-undang hak cipta nasional. Khusus dalam kaitannya dengan dasar-dasar pembentukan sistem ekonomi Nasional, yang menjadi rujukan adalah sila ke lima dari Pancasila. Nilai filosofis dalam sila kelima antara lain didalamnya tersirat nilai keadilan dan nilai kesejahteraan yang dikenal dengan sistem ekonomi kerakyatan. 219 Kesejahteraan yang dicapai oleh masyarakat Indonesia hendaklah didistribusikan secara adil dan merata bagi kemakmuran rakyat. Sumber-sumber kehidupan ekonomi harus ditata dengan baik secara berkeadilan. Pengaturan sumber-sumber ekonomi itu dapat dituangkan dalam undang-undang yang menyerap dan merespon nilai-nilai keadilan. Seluruh undang-undang yang bersentuhan dengan praktekpraktek ekonomi seperti kepemilikan tanah, penanaman modal asing, pemanfaat hasil tambang, pemanfaatan sumber daya hutan dan kelautan dan sumber-sumber bahan tambang dan lain sebagainya yang melahirkan hak-hak ekonomi harus bermuara pada nilai keadilan tidak terkecuali undang-undang hak cipta nasional yang menyangkut hak kekayaan intelektual. Di sisi lain sejarah perjalanan Undang-undang Hak Cipta Nasional sejak awal telah diwarnai oleh nilai filosofis peradaban dunia Barat yakni individualis, kapitalis dan liberal. 220 Hasilnya adalah undang-undang hak cipta nasional terakhir ini adalah merupakan kompromi politik nasional dengan masyarakat internasional. Inilah yang menurut Christopher May 221 sebagai politik ekonomi global dalam bidang intellectual property rights. 219 Lebih lanjut lihat Djoko Dwiyanto dan Ignas G. Saksono, Ekonomi (Sosialis) Pancasila Vs Kapitalisme Nilai-nilai Tradisional dan Non Tradisional Dalam Pancasila, Keluarga Besar Marhenisme, Yogyakarta, 2011. 220 Auteurswet 1912 Stb. No. 600 berasal dari hukum Kolonial Belanda dengan latar belakang filsafat yang demikian. Dalam perjalanan selanjutnya, undangundang hak cipta nasional pasca ratifikasi GATT 1994/WTO yang didalamnya memuat TRIPs Agreement mengharuskan pula Indonesia untuk menyesuaikan undang-undang hak cipta nasionalnya dengan instrument hukum yang berlatar belakang ideologi kapitalis liberal. 221 Christopher May, The Global Political Economy of Intellectual Property Rights, The new enclosures Second Edition, Routledge, London, 2010. 305 Negara Indonesia pada saat menyusun Undang-undang Hak Cipta No. 7 Tahun 1987 merevisi Undang-undang Hak Cipta No. 6 Tahun 1982 bukanlah berada pada posisi negara produsen yang maju dalam penciptaan program komputer. Perusahaan-perusahaan dalam bidang Information Technology dan perusahaan yang memproduksi soft were komputer belum ada di Indonesia akan tetapi pada tahun itu Indonesia harus memasukkan satu klausul tentang itu (perlindungan program komputer) dalam undang-undang hak ciptanya. Ini menimbulkan sebuah pertanyaan yang besar : Apakah masuknya klausul itu semata-mata karena perlindungan karya cipta ini sudah merupakan kebutuhan masyarakat Indonesia ketika itu ? Atau justru masuknya bidang ini karena adanya tekanan atau pesanan dari negara lain yang mempunyai kepentingan atas perlindungan karya ciptanya di bidang ini. Tidak diperoleh keterangan yang jelas latar belakang masuknya ketentuan ini dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1987, tetapi yang pasti sebelum undang-undang ini lahir, Presiden Soeharto mengadakan pembicaraan empat mata dengan Presiden Ronald Reagen di Bali. Inti pembicaraannya adalah Indonesia harus merobah undangundang hak cipta nasionalnya yang berlaku pada waktu itu. Hasil pertemuan itu kemudian disikapi oleh Pemerintah Soeharto dengan membentuk satu tim yang diberi tugas untuk menyusun Undangundang Hak Cipta Indonesia yang memiliki standard internasional. Selepas pertemuan itu terbentuklah Tim Kerja Khusus yang diketuai oleh : Moerdiono yang kala itu menjabat sebagai Menteri Sekretaris Kabinet berdasarkan Keputusan Presiden tangal 30 Juli 1986. Tim ini kemudian melakukan berbagai aktivitas untuk mengumpulkan informasi bekerjasama dengan berbagai universitas menyelenggarakan seminar dan berujung pada penyusunan rancangan undang-undang perubahan atas Undang-undang Hak Cipta No. 6 Tahun 1982. Rancangan undang-undang itu disampaikan kepada DPR pada bulan Juni dan ditetapkan menjadi undang-undang pada tanggal 9 September 1987 dan mulai berlaku pada tanggal 19 September 1987. 222 Dalam penjelasan Undang-undang No. 7 Tahun 1987 hanya dikatakan, program komputer atau computer program yang merupakan bahagian dari perangkat lunak dalam sistem komputer pada dasarnya merupakan karya cipta ilmu pengetahuan dan itu perlu ditegaskan sebagai ciptaan yang layak diberi perlindungan sebagai hak cipta. Lebih lanjut penjelasan pasal demi pasal hanya menegaskan pengertian 222 Lebih lanjut lihat, OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 153. 306 program komputer sebagai peralatan elektronik yang memiliki kemampuan mengolah data dan informasi. Oleh karena itu dapat diyakini bahwa masuknya ketentuan pasal ini bukanlah karena kemajuan teknologi masyarakat Indonesia pada waktu itu sudah mencapai pada titik di mana karya cipta program komputer ini harus dilindungi oleh undang-undang, melainkan karena adanya permintaan negara-negara dimana warganya sebagai pemegang (pemilik) program komputer yang saat itu sudah dipasarkan di berbagai belahan dunia. Negara seperti Amerika, sudah barang tentu memiliki kekhawatiran terhadap Indonesia terlebih-lebih Cina yang mereka akui sendiri sebagai negara peringkat atas melakukan pembajakan hak cipta. Budaya untuk berbagi ilmu pengetahuan dan berbagi kenikmatan atas hasil yang telah dicapai oleh seseorang adalah budaya yang sudah terpatri dalam kultur masyarakat Indonesia. Dalam cerita hikayat lama, banyak dikisahkan tentang para saudagar yang pemurah. Demikian pula kisah-kisah tentang para guru yang berbagi ilmu dengan murid-muridnya. Para tabib yang mengobati pasien dari kalangan masyarakat yang sakit tanpa dipungut bayaran. Pendek kata, aspek nilai kekeluargaan dan nilai kebersamaan selalu diletakkan di atas kepentingan individual. 223 Masuknya paham individualis yang merasuk sendi-sendi masyarakat Indonesia pada kurun waktu dua dasawarsa terakhir ini tidak terlepas dari peranan negara-negara kapitalis liberal melalui kemajuan teknologi informasi dan teknologi transportasi yang membuat sekatan dinding antar negara semakin sempit dan terbangunnya tatanan ekonomi kapitalis dengan sistem merkantilisme. Ahli ekonomi politik Skotlandia Adam Smith 224 (1723-1790) menciptakan istilah “sistem merkantil” yang dia definisikan sebagai “mendorong ekspor dan tidak mendorong impor”. Asumsi normatif merkantilisme ialah bahwa kebijakan ekonomi hendaknya meningkatkan kekuatan negara, khususnya kekuatan militer. Di sini,kebijakan ekonomi kaum merkantilis berubah menjadi realitas politik. Kaum merkantilis percaya bahwa akumulasi emas dan perak sangat bermanfaat bagi persiapan cadangan devisa, namun tidak banyak manfaat yang didapat dari perdagangan logam mulia itu. Alasannya adalah karena logam mulia hanya digunakan untuk 223 Lihat lebih lanjut Kaelan, Negara Kebangsaan Pancasila Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya, Paradigma, Yogyakarta, 2013, hal. 397. WTO adalah mesin hukum penggerak menuju tatanan dimana liberal kapitalis. 224 Adam Smith, Lectures on Jurisprudence, Oxford University Press, New York, 1978. 307 menyeimbangkan pembayaran impor dengan nilai barang yang diekspor sebagai cadangan devisa agar tidak terjadi devisit anggaran. Karena setiap negara menerima logam mulia sebagai pembayaran untuk impor, logam mulia semacam itu menjadi dasar kekayaan. Kenyataannya, penumpukan logam mulia dengan tidak memproduksi barang sambil meningkatkan persediaan uang suatu negara sangat berbahaya bagi perekonomian suatu negara, karena tindakan itu akan berujung pada inflasi. Itulah sebabnya kaum merkantilis lebih mengarahkan kebijakannya pada penguatan politik ekonomi dan penguatan politik pertahanan negara. Memacu ekspor berarti menggiatkan produksi dan itu akan dapat diwujudkan melalui kebijakan industrialisasi. Semua kegiatan produksi digiring ke sektor industri. Mulai dari industri pertanian, perikanan, makanan, obat-obatan, kimia, kedirgantaraan, persenjataan, otomotif sampai pada industri hiburan antara lain dalam wujud industri perfilman. Semua ini menyangkut Hak kekayaan Intellektual. Sasaran ekspor adalah negara-negara berkembang atau negara dunia ketiga, yang relatif minim dalam kepemilikan dan penguasaan Hak Kekayaan Intelektual. Keadaan inilah yang memaksa kaum merkantilis kemudian melancarkan gerakan “pengamanan HKI” mereka melalui politik perdagangan dengan mendesain dan memanfaatkan instrumen Hukum Internasional. Karena hanya dengan cara ini menurut Hikmahanto 225 negara-negara maju dapat terhindar dari tuduhan mengintervensi kedaulatan suatu negara yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum Internasional. Kesepakatan perdagangan yang tertuang dalam GATT1994/WTO dengan instrumen ikutannya antara lain TRIPs Agreement adalah satu contoh saja, bagaimana kaum merkantilis memainkan peranan politik ekonomi dan politik pertahanan negaranegara yang tergabung dalam negara Industeri maju di bawah rancangan Amerika. Tidak hanya membatasi tentang pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual melalui kewajiban untuk menyesuaikan undangundang HKI di negaranya dengan TRIPs Agreement dan seluruh Konvensi Internasional terkait, tetapi juga membuat klausule tentang larangan import paralel226 yang berujung pada perlindungan negara produsen sebagai pemilik HKI. 225 Lebih lanjut lihat Hikmahanto Juwono, Orasi Ilmiah Hukum Sebagai Instrumen Politik : Intervensi atas Kedaulatan Dalam Proses Legislasi di Indonesia, Disampaikan pada Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Ke-50, 12 Januari 2004. 226 Lebih lanjut lihat M.Hawin, Intellectual Property Law on Parallel Importation, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2010. 308 Sejarah merkantilis demikian 227 tak terlepas dari sejarah peperangan yang diawali dari persaingan kolonial di antara sesama negara-negara di Eropa. Penaklukan Spanyol atas Amerika Selatan dan Tengah pada abad ke-16 dan akses negara itu pada logam mulia menjadikan negara itu sebagai adidaya pada abad itu, dan koloni-koloni dunia barunya menjadi bagian dari blok perdagangan kerajaan-kerajaan besar yang berkuasa pada waktu itu. Pada tahun 1600, “Kerajaan Amerika – Spanyol “ yang terdiri atas Spanyol Baru (daratan utama di utara Genting Tanah Panama, West Indies dan Venezuela) dan Peru (Amerika Selatan di selatan Spanyol Baru kecuali Brazil), masingmasing diperintah oleh salah satu wakil pribadi raja atau raja muda. Merkantisme Spanyol melarang negara-negara asal non Spanyol mengunjungi koloni-koloni Spanyol, melarang ekspor asing dari koloni-koloninya dan menuntut agar ekpor ke koloni-koloninya diekspor kembali melalui Spanyol. Disamping itu, koloni-koloni Spanyol tidak diizinkan membuat berbagai produk. Dan sampai tahun 1720 semua perdagangan koloni harus diekspor kembali melalui Kota Seville. Di bawah merkantilisme, hubungan ekonomi dan politik terjalin dengan baik. Kaum merkantilisme menganggap bahwa tarif terhadap impor merupakan sumber utama pendapatan pemerintah untuk membayar senjata dan tentara. Untuk tujuan ini, raja-raja Eropa selalu campur tangan dalam perekonomian negara-negara mereka, dengan mengatur produksi barang yang berhubungan dengan keamanan dan membangun monopoli negara, korporasi-korporasi dan perusahaanperusahaan dagang. Kaum merkantilisme juga mendukung ekspansi kerajaan dan pendirian koloni-koloni di luar negeri untuk memperoleh pasar yang lebih besar bagi produk mereka dan akses eksklusif pada sumber-sumber bahan-bahan mentah yang penting bagi kegiatan industeri negara mereka. Di samping itu, indusetri manufaktur yang menghasilkan produk terbaru diberi monopoli di luar negeri, sedangkan pesaing-pesaing potensial dilarang masuk ke pasar dalam negeri dan pasar kolonial melalui kuota, tarif, dan larangan import. 228 Inilah awal sejarah ekonomi kaum merkantilis yang menjadi cikal bakal era perdagangan bebas yang diusung oleh WTO ketika 227 Lebih lanjut lihat Eamonn Kelly, Agenda Dunia Powerful Times Abad 21, Bangkit Menghadapi Tantangan Dunia Yang Penuh Ketidakpastian, Index, Jakarta, 2010. 228 Richard W. Mansbach & Kirsten L. Rafferty, Pengantar Politik Global Introduction to Global Politics, Terjemahan Amat Asnawi, Nusamedia, Bandung, 2012, hal. 606-608. 309 imperialis dan kolonialis tidak lagi menjadi pilihan politik di era pasca Perang Dunia II, namun bentuk dan model penjajahan ekonomi dan penjajahan politik belum berubah dan masih terus berlanjut hingga hari ini. Yang berubah adalah cara negara-negara maju itu melancarkan politik imperialis-nya, misalnya dengan memanfaatkan instrumen hukum internasional. Negara-negara yang menjadi sasarannya harus terus menerus menyesuaikan diri dengan tuntutan mereka, melalui adaptasi atau dengan cara-cara “politik balas budi” misalnya melalui pinjaman hutang luar negeri yang sumber keuangannya berasal dari negara-negara maju tersebut. Bagian dari proses adaptasi pasti akan mencakup urgensi yang lebih besar untuk memperbaiki modal-modal pasar untuk menguntungkan mereka yang bertarung. Kadang-kadang, langkah adaptasi itu menggiring negara yang bersangkutan ke dalam kapitalisme yang baru. Ahli ekonomi Peruvian, mengemukakan bahwa Hernando de Soto 229 memperdebatkan dalam The Mystery of Capital bahwa negara Barat telah mengembangkan jaringan hukum, pengharapan, gelar, serta hubungan tak terencana dan tak terlihat yang mendukung kepemilikan properti, dan ini mendorong terbentuknya sistem ekonomi kapitalis. Namun, di banyak negara berkembang, elemen vital dari sistem itu tidak muncul – hal ini bukanlah fakta yang mengejutkan, karena sebagian besar orang di Barat memahami secara terbuka cara sistem mereka bekerja. Sebagai hasilnya, de Soto mengklaim bahwa usaha dengan niat baik yang dilakukan dana moneter internasional IMF, bank dunia dan agen-agen lain yang menyebarkan model kapasitas modern benar-benar gagal atau sukses yang tertunda. De Soto mengacu pada rezim Hak Kekayaan Intelektual yang memaksakan sebagai salah satu faktor pencetus sistem kapitalisme. Dia memperkirakan bahwa dalam dunia berkembang sekarang ini 8 milyar dolar tersia-sia kan tak tereksploitasi, dalam bentuk harta informal – kapital yang potensial, yang bisa untuk menghasilkan kesejahteraan baru dan kesempatan. Dia telah menyarankan pemikiran konkrit, kebijakan dan tindakan untuk melepaskan kemungkinan laten (tersembunyi) yang sangat besar. Argumennya menarik sebuah perhatian yang besar, dan mantan presiden Amerika Bill Clinton menyebut pandangannya sebagai pengembangan ekonomi sistematik yang paling signifikan selama bertahun-tahun. Ide-ide ini menginformasikan secara pasti perdebatan dan pengaruh kebijakan pada dekade globalisasi berikutnya. Negara maju telah sangat diuntungkan dari perdagangan global selama lebih dari seabad. Tetapi hal ini tidak dapat dihentikan dan akan terus berlanjut, hanya dengan pengenalan aspirasi legitimasi dari seluruh dunia untuk menjadi mitra sejati dan peserta dalam ekonomi global yang sedang berkembang. Hal ini pasti mengharuskan negara maju, untuk memberikan pijakan dasar bagi dukungan terhadap sektor-sektor ekonomi negara berkembang seperti sektor pertanian, kelautan dan lain sebagainya. Hal ini juga mengharuskan negara maju memberikan kontribusi berupa bantuan modal, tenaga ahli dan teknologi yang dibutuhkan negara berkembang, Bantuan itu di 229 Hernando De Soto, The Mystery of Capital Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else, Basic Books, New York, 2000, hal. 35-36. 310 semestinya diberikan ke seluruh sektor ekonomi termasuk transfer teknologi termasuk teknologi tinggi, akan tetapi hal itu untuk kasus Indonesia tidak terjadi yang ada hanyalah pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia yang relatif belum “terjamah” dan dapat t menyediakan buruh murah dan pasar konsumen yang besar.230 Dekade berikutnya seharusnya menghasilkan pencapaian positif sehingga kemakmuran si kaya sama dengan si miskin sama rata. Namun, akan ada tantangan serius untuk ke depannya dan dunia maju harus memulai proses yang menyakitkan untuk melepaskan pemahaman tentang apa yang diyakininya sebagai langkah politik ekonomi yang benar. Hasilnya adalah, sementara jutaan orang diuntungkan dari penyebaran kemakmuran, jutaan lainnya akan mengalami sebaliknya : kemerosotan standar hidup. Bagi orang banyak, hal ini akan menjadi mutlak – kemerosotan yang begitu memilukan dari apa yang mereka ketahui sebelumnya. Bagi orang lain, hal ini relatif ; hal ini akan datang dalam bentuk rasa sakit untuk tetap bertahan atau hanya bergerak maju sedikit sementara yang lain berpacu di depan. Menurut PBB, jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan (yaitu orang-orang yang hidup dengan uang kurang dari 1 dolar sehari) menurun. Tetapi, masih terdapat 1,3 milyar orang miskin – kasarnya, seperempat dari populasi dunia. Tujuan pengembangan milenium PBB berjanji untuk mengurangi jumlah tersebut pada tahun 2015 dan kemajuan sedang diusahakan untuk tujuan ini. Namun, data lain menyatakan bahwa kondisi orang miskin sebenarnya semakin memburuk. Selain usaha-usaha institusi internasional seperti Bank Dunia, IMF, dan PBB, dan usaha peningkatan beberapa perusahaan global, 21 negara di seluruh dunia meninggakan tahun 1990-an dengan menurunnya tingkat perkembangan. Sedangkan selama tahun 1980-an hanya 4 negara diketahui oleh program pengembangan PBB yang menunjukkan kemerosotan dekade jangka panjang yang serupa. 231 Grafik di bawah ini, menunjukkan ketimpangan ekonomi di berbagai negara di dunia. 230 Lihat Andi Makmur Makka, Jejak Pemikiran B.J. Habibie Peradaban Teknologi Untuk Kemandirian Bangsa, Mizan, Yogyakarta, 2010. Bagaimana kemudian IMF dalam LoI nya membatasi penggunaan dana bantuan IMF untuk pengembangan industrei strategis yang dibangun oleh Habibie yang akhirnya kandas dan Indonesia mundur 30 tahun dalam sektor ini. 231 Eamonn Kelly, Agenda Dunia Powerful Times Abad 21, Bangkit Menghadapi Tantangan Dunia Yang Penuh Ketidakpastian, Index, Jakarta, 2010, hal. 171-173 311 Grafik 1 Ketimpangan Ekonomi di Berbagai Dunia GNP Populasi GNP per kapita 5,9% 3,8% 2,8% 2,6% 1,8% 1,4% 1,9% 1,7% 2,1% 0,7% -0,9% -0,4% Negara dengan pendapatan rendah Negara dengan pendapatan rendah termasuk Cina dan India Negara dengan pendapatan menengah Negara dengan pendapatan tinggi Terjadinya ketimpangan ekonomi ini tidak terlepas dari pilihan negara maju dalam melancarkan politik ekonomi globalnya. Amerika dengan kebijakan politik ekonominya yang tertuang dalam “Konsensus Washington” justru telah menciptakan ketidak stabilan ekonomi dan membangkitkan rasa ketidak adilan di beberapa negara. Banyak tuduhan yang diarahkan kepada IMF dan Bank Dunia yang menganggap bahwa kedua lembaga keuangan internasional ini telah merekayasa aturan main hanya untuk melayani kepentingan negara kaya daripada negara miskin. Tidak kurang dari mantan Kepala Ekonomi Dunia yang juga peraih Nobel dalam bidang ekonomi Joe Stiglitz, mengatakan dengan jelas : “Globalisasi telah menciptakan banyak negara miskin di dunia yang kemudian tumbuh menjadi lebih 312 miskin. Bahkan ketika keadaan mereka membaik justru pada saat yang sama mereka merasa lebih lemah. 232 Itulah pilihan kapitalis, yang membawa konsekuensi yang sesungguhnya tidak terlihat secara kasat mata akan tetapi menimbulkan kerumitan, ketidak adilan dan sesungguhnya berbahaya juga bagi kelangsungan kehidupan umat manusia. 233 Kapitalis mungkin hanya dapat memacu pertumbuhan ekonomi tapi tidak dapat memacu pemerataan. Moises Naim 234 menunjuk dalam pilihan ekonomi kapitalis menghadapi globalisasi yang harus dilawan oleh otoritas nasional adalah perdagangan narkoba, perdagangan illegal persenjataan, pembajakan hak kekayaan intelektual, penyeludupan antar negara dan pencucian uang. Globalisasi, demikian Naim mencatat membuat dunia semakin saling berhubungan dan jaringan kriminal juga memasuki aliansi strategi melintasi budaya dan melintasi benua. Kapitalis dan globalisasi telah berjalan beriringan. Kapitalis menekankan pada strategi dan kebijakan menanamkan faham ekonomi, sementara globalisasi adalah kenderaan yang digunakan untuk menyebarkan faham itu. Karena keberhasilan kapitalis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun di sisi lain kegagalannya dalam menciptakan pemerataan serta memelihara moral dan peradaban, maka tawaran ideologi “penyeimbang” haruslah dijadikan sebagai alternatif. Indonesia dengan ideologi Pancasila telah menawarkan sebuah gagasan besar dalam konsep ideologi pembangunan dalam bidang ekonomi yakni ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. Kesejahteraan dalam bidang ekonomi harus diimbangi dengan pemerataan. Pemerataan adalah wujud dari nilai keadilan. Sila kelima Pancasila memuat nilainilai filosofis yang dapat dijadikan kerangka acuan dalam pilihan politik ekonomi. 232 Ibid, hal. 174. Pilihan terhadap kapitalis memang sebahagian telah menciptakan negaranegara miskin meraih kehidupan yang lebih baik. Akan tetapi keadaan itu hanya dinikmati oleh segelintir orang. Warga miskin semakin hari semakin meningkat. Ada sejumlah orang tua yang kaya raya tapi ditemukan sejumlah anak muda lainnya yang hidup dalam kemiskinan. Negara-negara maju yang bertumpu pada pilihan kapitalis ini juga terlihat maju secara ekonomis akan tetapi dalam kualitas kehidupannya justru memperlihatkan kemunduran. Sebaran virus HIV telah menggerogoti kehidupan sejumlah anak-anak muda di negara-negara maju. Kecanduan alkohol dan obat-obatan terlarang telah mewabah di seluruh dunia sebagai akibat dari pilihan kapitalis yang didorong oleh arus globalisasi. Lebih lanjut lihat Ibid, hal. 175-176. 234 Lebih lanjut lihat Ibid, hal. 93 233 313 Begitupun pilihan semacam itu tidak ditemui manakala dirujuk Undang-undang Hak Cipta Nasional yang sejak awal telah dipenuhi oleh muatan-muatan kapitalis. Gagasan-gagasan yang tertuang dalam Undang-undang Hak Cipta Nasional yang kemudian dijelmakan kedalam pasal demi pasal telah memperlihatkan, betapa faham kapitalis itu telah tertanam. Sebagai contoh : Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 19 Tahun 2002 menguatkan anggapan bahwa pesan-pesan negara maju yang memenangkan pertarungan Uruguay Round untuk kemudian dituangkan dalam kesepakatan GATT 1994/WTO yang melahirkan TRIPs Agreement telah ditransplantasikan secara sempurna. Meskipun dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002 terdapat pasal-pasal yang masih mengacu kepada tatanan nilai keadilan dan ekonomi kerakyatan seperti Pasal 16 yang mengatur tentang pemberian imbalan terhadap pencipta sekalipun ciptaan itu digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan serta kegiatan penelitian dan pengembangan. Pasal 18 juga memperhatikan segi-segi dari nilai ekonomi kerakyatan yakni tetap memberikan imbalan yang layak atas ciptaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Nilai keadilan juga tercantum dalam Pasal 26 yang meletakkan keseimbangan hak atas penjual dan pembeli atas hak cipta dalam hubungan jual beli. Demikian juga Pasal 45 menegaskan tentang pemberian royalty kepada pemegang hak cipta dalam hal lisensi. Namun di sisi lain lisensi telah menjadi alat atau instrumen ekonomi kapitalis yang menyebabkan ketergantungan para pelaku ekonomi dengan pemegang hak cipta. Tentu saja jika hal ini terjadi menyebabkan hanya mereka-mereka yang memiliki posisi sebagai pemegang hak cipta yang dapat menikmati secara leluasa tentang ciptaan yang dihasilkannya sedangkan masyarakat luas baru dapat menikmatinya melalui mekanisme lisensi. Tampaknya jurang pemisah yang melebar antara masyarakat kaya dan miskin telah disumbangkan dengan baik oleh pilihan ekonomi kapitalis. Penegasan tentang hal itu dapat dilihat dari penjelasan Pasal 2 yang menegaskan pihak lain tidak boleh memanfaatkan hak cipta tanpa ijin pemegangnya dan itu tidak hanya meliputi tentang penyewaan tetapi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan hak cipta meliputi pengumuman dan perbanyakan termasuk kegiatan penterjemahan mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewa, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun padahal syarat semacam ini tidak diharuskan oleh TRIPs Agreement. 314 Terlihat nyata bahwa Undang-undang No. 19 Tahun 2002 semakin bergeser ke arah kapitalis yang membawa dampak semakin menurunnya kualitas kehidupan di banyak negara yang masih terdapat penduduk miskin seperti Indonesia. Kemerosotan moral dan pelanggaran hukum akhirnya menjadi bahagian yang tak terhindarkan. Jika dari waktu ke waktu undang-undang hak cipta nasional disempurnakan dan dari waktu ke waktu pula ancaman pemidanaan terhadap pelanggaran hak cipta semakin diperberat, akan tetapi dari waktu ke waktu pula pelanggaran atau pembajakan hak cipta tidak pernah berhenti dan dari waktu ke waktu memperlihatkan peningkatan secara kuantitatif. G. Analisis dan Temuan Nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila sebagai abstraksi dari nilai-nilai the original paradigmatic value of Indonesian culture and society yang dijadikan sebagai dasar kebijakan politik hukum nasional (sebagai landasan filosofis), yang merupakan grundnorm sebahagian besar terabaikan dalam proses pembentukan Undang-undang Hak Cipta Nasional mulai masa Kolonial Belanda dengan politik hukum Eropanisasi hukum ke wilayah jajahan melalui kebijakan penerapan azas konkordansi (Persamaan hak, pernyataan berlaku dan tunduk sukarela) dan diteruskan pada masa kemerdekaan, dengan politik hukum transplantasi hukum asing. Nilai-nilai filsafati Pancasila yang sebagian terabaikan adalah Nilai Ketuhanan yang Maha Esa bergeser dan berubah ke nilai sekularisme, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab digantikan dengan nilai faham individualis, nilai Persatuan atau nilai kebangsaan digantikan dengan nilai imperalisme tersembunyi, nilai Kerakyatan dan nilai musyawarah mufakat digantikan dengan nilai demokrasi liberal, nilai Keadilan Sosial dan nilai kesejahteraan dalam bidang ekonomi digantikan dengan nilai kapitalis. Perubahan dan pergeseran nilai-nilai ini terjadi karena kebijakan Politik Hukum Indonesia (tidak hanya dalam lapangan hak cipta) yang dipilih dipengaruhi oleh perjalanan sejarah bangsa ini yang selama tiga setengah abad berada di bawah koloni Kerajaan Belanda yang dalam berbagai kesempatan menanamkan missi Politik Hukum yang telah dirancang secara sistematis sejak awal, akan tetapi juga pasca kemerdekaan Indonesia lebih memilih pada kebijakan politik hukum pragmatis, sehingga nilai-nilai filsafati Pancasila itu nyaris (menjadi) terabaikan. 315 Jika dibandingkan dengan teori negara hukum modern yang dianut oleh Indonesia, maka Undang-undang Hak Cipta Nasional yang akan menjadi rujukan dalam perilaku penegakan hukum mestinya sejak awal harus didesain dalam politik hukum nasional untuk dapat menampung aspirasi masyarakat Indonesia yang mengacu pada landasan ideologi Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Secara substantif isi undang-undang hak cipta nasional itu seharusnya menampung gagasan ideal cita-cita negara yang dirumuskan sebagai tujuan negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur atau negara sejahtera (welfare state). Undang-undang Hak Cipta Nasional yang sesuai dengan tujuan negara itu diturunkan menjadi policy (kebijakan) yang dijadikan sebagai wawasan politik hukum nasional yang dituangkan dalam program legislasi nasional (prolegnas) sebagai garis politik pembangunan hukum nasional di bidang hak cipta. Dalam tataran praktek undang-undang ini dijadikan sebagai rujukan dalam aktivitas penegakan hukum (law enforcement). Tulisan ini telah membuktikan bahwa baik pada tahapan pembentukan undangundang sampai pada tahapan penerapannya menyimpang dari teori negara hukum. Sehingga untuk kasus pelaksanaan undang-undang hak cipta dalam bidang perlindungan karya sinematografi tidak lagi memperlihatkan adanya nuansa-nuansa negara hukum akan tetapi lebih banyak memunculkan pada konsep negara kekuasaan. Pada tataran middle range theory, Seidman mengatakan bahwa the law of non transferability of law bahwa auteurswet 1912 Stb. No. 600 dan TRIPs Agreement beserta konvensi-konvensi internasional yang menjadi ikutannya tidaklah tumbuh dari peradaban bangsa Indonesia. Sehingga ketika transplantasi hukum itu dilakukan (transfer of law) ternyata banyak nilai-nilai (the original paradigmatic value of Indonesian culture and society) yang hilang yang tidak tertampung dalam undang-undang hak cipta nasional ini. Saat undang-undang hak cipta nasional hasil transplantasi itu diterapkan ternyata tertolak dalam masyarakat. Proses penolakan itu berjalan secara masif dengan proses pembiaran struktural. Tidak ada penegakan hukum yang berarti yang dilakukan guna menegakkan norma-norma undang-undang hak cipta nasional khususnya dalam bidang karya sinematografi. Budaya penegakan hukum sama sekali tidak mencerminkan gagasan-gagasan negara hukum. Hal itu terjadi karena transplantasi norma hukum tidak diikuti dengan transplantasi struktur dan kultur. Normanya berasal dari peradaban Barat, tapi struktur dan kultur masih kental dengan warna Indonesia dengan peradaban Timur. 316 Undang-undang hak cipta nasional mengacu pada pada teori politik hukum Hikmahanto Juwana pada tataran basic policy yang semula diarahkan untuk menjadi sarana yang dapat menumbuhkan kreativitas pencipta khusus dalam lapangan karya sinematografi diarahkan untuk mewujudkan industri perfilman nasional menjadi industri kreativitas yang dapat mendongkrak kesejahteraan ekonomi sosial dan masyarakat Indonesia, justru tidak mencapai tujuannya. Pada tataran basic policy dan anactment policy yang terjadi adalah undangundang hak cipta nasional telah melumpuhkan sendi-sendi peradaban karena praktek pembajakan dan pelanggaran hak cipta telah membuat industri perfilman nasional menjadi tidak tumbuh. Bahkan para seniman banyak yang memilih untuk beralih menjadi aktor politik. Kenyataan ini membuktikan bahwa hukum yang semula bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan ternyata kemudian menjadi komoditi politik dalam tataran anactment policy sehingga hukum tidak dapat ditegakkan yang akhirnya hanya memberi makna simbolik (symbolic meaning). Hukum yang ditempatkan sebagai sub sistem dalam sistem politik nasional dan sistem politik berada bersama-sama dengan sub sistem lainnya dalam sistem nasional memberikan jawaban bahwa ternyata hukum tidak berada pada ruang hampa. Faktor yang mengelilingi atau mengitari tempat dimana hukum itu diciptakan dan diberlakukan pada akhirnya akan menentukan keberadaan hukum itu dalam sistem nasional. Dengan meminjam kerangka skema sistem politik hukum Indonesia menurut analisis kesisteman dari M. Solly Lubis maka dapat dipastikan bahwa kualitas politik hukum sebagai sub sistem dalam sistem politik nasional akan menentukan jalannya sistem politik. Sebagai suatu sistem ini akan berpengaruh pula terhadap kualitas ketahanan nasional. Dalam kasus transplantasi hukum asing ke dalam undang-undang hak cipta nasional memperlihatkan bahwa pilihan politik yang dilakukan adalah pilihan politik yang sangat pragmatis dan itu akan mempengaruhi dimensi hukum secara internal yakni akan menggusur nilai-nilai hukum lokal (act locally) sedangkan secara internal dimensi hukum internasional (Auteurswet 1912 Stb. No. 600 dan TRIPs Agreement) cukup kuat berpengaruh baik secara ideologis maupun secara normatif terhadap hasil akhir undang-undang hak cipta nasional. Dalam dimensi internal terlihat bahwa pilihan politik hukum transplantasi yang bersifat pragmatis itu secara meyakinkan berpengaruh pada ideologi politik yakni bergesernya dari ideologi Pancasila ke ideologi liberal. Pada tataran sub sistem ekonomi terjadi 317 pula pergeseran dari sistem ekonomi kerakyatan bergeser kepada sistem ekonomi kapitalis, sedangkan pada tataran sosial budaya terjadi kegoncangan budaya (culture shock) yang ditandai dengan penolakan terhadap nilai-nilai yang ditawarkan oleh sistem hukum asing (Auteurswet 1912 Stb. No. 600 dan TRIPs Agreement) yakni penegakan undang-undang hak cipta khususnya dalam bidang karya sinematografi tak pernah dapat ditegakkan. Budaya legislatif, eksekutif, yudikatif dan masyarakat tak pernah mampu menyahuti norma-norma hukum yang nilai-nilainya (bahkan normanya) di transplantasi dari hukum asing. Pada tataran pertahanan dan keamanan terjadi pelemahan pada fungsi penegakan hukum yang berdampak juga terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum. Semakin melemahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, maka semakin lemah pula sistem pertahanan dan keamanan. Dampak konstruktif yang dihasilkannya adalah, Indonesia mempunyai undang-undang hak cipta nasional yang memiliki standarisasi internasional, akan tetapi dampak yang destruktif tak bisa tidak akan muncul. Dampak destruktif yang terjadi adalah terjadi pelemahan pada ideologi, ekonomi, sosial budaya dan hankam yang pada gilirannya akan menghilangkan jati diri bangsa. Secara ekonomi kesadaran akan ekonomi kerakyatan semakin kering dari nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila. Dampak konstruktif yang dihasilkannya adalah, Indonesia mempunyai undang-undang hak cipta nasional yang memiliki standarisasi internasional, akan tetapi dampak yang destruktif tak bisa tidak akan muncul. Dampak destruktif yang terjadi adalah terjadi pelemahan pada ideologi, ekonomi, sosial budaya dan hankam yang pada gilirannya akan menghilangkan jati diri bangsa. Secara ekonomi kesadaran akan ekonomi kerakyatan semakin kering dari nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila. Temuan berikutnya adalah dengan menggunakan skema kerjasama teoritis dan praktisi dalam pembinaan hukum nasional maka kerjasama antara teoritis dalam bidang politik, hukum, ekonomi, budaya dan lain-lain dalam sistem nasional akan dapat dipadukan dengan kalangan praktisi dalam sub bidang yang sama. Secara ideal dalam pandangan teoritis, politik, hukum, ekonomi dan budaya haruslah mengacu pada cita-cita negara Republik Indonesia yang bersandar pada ideologi Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 akan tetapi dalam tataran praktek politik disimpangi karena adanya tuntutan pragmatis yang berpengaruh terhadap kebijakan pembentukan hukum yang tidak dapat lagi terhindar dari tuntutan 318 pragmatis itu. Kesemua ini akan membawa dampak dalam tataran praktis terhadap komponen-komponen ekonomi dan budaya. Akan tetapi, pandangan dari sudut teoritis tersebut hendaklah dipadukan dengan pandangan dari sudut pengalaman praktis sehingga keduanya dapat dipadukan guna merumuskan hukum nasional yang dapat menyeimbangkan antara gagasan ideal (teoritis) dengan kepentingan praktis yakni dalam konteks undang-undang hak cipta melahirkan gagasan undang-undang hak cipta nasional yang dapat melindungi kepentingan dan menumbuhkan kreativitas anak bangsa selaku pencipta, akan tetapi dapat pula menyahuti kepentingan-kepentingan yang bersifat praktis dalam suasana pergaulan antar bangsa. Pilihan terhadap politik hukum tidak lagi semata-mata dilakukan dengan pilihan yang didasarkan pada kebutuhan sesaat (pragmatis) akan tetapi juga melihat pada kebutuhan jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan nasional. Kesemua ini dapat disusun dalam wawasan politik hukum yang dijadikan sebagai dasar prolegnas dan relegnas. Dengan demikian undang-undang hak cipta nasional yang selama kurun waktu 4 kali masa perubahan itu diteliti ulang kembali bahagianbahagian mana yang perlu mendapat perhatian guna menyahuti gagasan-gagasan ideal dan kepentingan praktis dan itu dapat diajukan dalam rancangan undang-undang penyempurnaan undang-undang hak cipta nasional di masa-masa yang akan datang. Rancangan undangundang itu untuk kemudian digodok di lembaga legislatif untuk dijadikan undang-undang. Pada tataran praktek diberlakukan undangundang hak cipta nasional yang baru. Pengalaman selama ini terlihat bahwa undang-undang hak cipta nasional yang berlaku dalam kurun waktu + 100 tahun memperlihatkan sisi penegakan hukum yang tidak menggembirakan. Hasil penelitian ini telah mengevaluasi pemberlakuan undang-undang hak cipta nasional itu dan itu dapat dijadikan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan undang-undang yang lebih menyahuti gagasan ideal (teoritis dan kepentingan praktis) semua ini akan dapat dijadikan sebagai umpan balik bagi kebijakan politik hukum pada masa-masa berikutnya. Sebahagian dari nilai ideologi Pancasila telah mati dan terkubur di tangan anak bangsa sendiri. Mati dan terkuburnya sebagian dari nilai-nilai ideologi Pancasila itu serta hidupnya ideologi kapitalis di Indonesia patut dicermati dan disikapi oleh siapapun yang cinta negeri dan bangsa ini. Undang-undang hak cipta yang menjadi obyek studi ini adalah sebahagian kecil dan salah satu contoh saja terhadap pilihan politik transplantasi hukum asing ke dalam undang-undang nasional. undang-undang lingkungan hidup, undang-undang 319 perlindungan konsumen, undang-undang perbankan, undang-undang penanaman modal, undang-undang perpajakan dan sederetan undangundang lainnya adalah undang-undang yang lahir dari pilihan politik hukum transplantasi hukum asing ke dalam undang-undang nasional. Pilihan politik yang pragmatis yang memiliki kecenderungan mengabaikan nilai-nilai ideologi negara dan bangsa, mengorbankan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia (act locally), dan telah mematikan serta mengubur nilai sosio-kultural the original paradigmatic value of Indonesian culture and society. Setiap kaedah atau norma hukum yang berlandaskan pilihan politik pragmatis tersebut lambat laun akan ditinggalkan dan dilupakan oleh masyarakat karena tidak ada yang perlu diingat dan dikenang dari pilihan politik yang seperti itu. Oleh karena itu perlu dilakukan uji materil terhadap beberapa pasal undang-undang Hak Cipta Nasional Undang-undang No. 19 Tahun 2002, diikuti dengan uji materil terhadap beberapa undangundang nasional lainnya, agar bisa kembali ke dasar filosofi bangsa yakni Pancasila sebagai grundnorm dengan mengembalikan jati diri bangsa yang terejawantah dalam undang-undang yang memuat secara substantif the original paradigmatic value of Indonesian culture and society. 320 BAB IV PILIHAN POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NASIONAL A. Pengantar Pilihan politik hukum kodifikasi parsial yang dikukuhkan sebagai politik pembangunan hukum nasional agaknya berjalan secara simetris dengan pilihan politik hukum transplantasi. Kodifikasi parsial adalah sebuah policy yang dipilih untuk menjawab keinginan bahwa Indonesia harus sebanyak mungkin membuat kaedah hukum tertulis yang dibukukan dalam kitab undang-undang, pasca negara ini berdiri sebagai negara yang merdeka. Kaedah hukum itupun harus berlaku secara unifikasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sejatinya masih berada dalam suasana pluralisme. Di sana sini sebahagian masyarakat hidup dalam suasana alam kehidupan modern di perkotaan dengan pola pemahaman “hukum modern” dan sebagian lainnya hidup dalam suasana kehidupan tradisional di pedesaan dengan pola pemahaman “hukum tradisional” di bawah payung hukum yang sama. Perbedaan pada pola pemahaman hukum, akan berbeda pula pada pilihan perilaku dalam menyikapi peraturan perundang-undangan yang sama. Kenyataan itu jugalah yang dalam perjalanan sejarah hukum bangsa ini pada masa dan oleh Pemerintah Hindia Belanda gagal dalam menerapkan politik hukum Eropanisasinya, karena adanya kenyataan pluralisme dalam masyarakat. Kegagalan itu justeru datang dari anak bangsanya sendiri, yakni seorang van Voellenhoven yang diikuti oleh muridnya Ter Haar yang menentang kebijakan politik hukum Eropanisasi karena menurut mereka pada masyarakat Negara Hindia Belanda itu ada norma hukum yang hidup yang diterima dan dijalankan sebagai hukum yang di kemudian hari oleh Snouck Hurgronje di sebutnya sebagai Adat Rech yang terdiri, Goddienstig Wetten, Volksinstelingen, Gubreiken. 235 235 Kenyataan inilah yang kemudian memaksa (tentu dengan didahului oleh berbagai kritik dan perlawananan terutama oleh van Voellenhoven) Pemerintah Hindia Belanda harus mengakui pluralisme hukum dengan mengukuhkannya dalam berbagibagai peraturan di Negara Hindia Belanda ketika itu. Lebih lanjut lihat Soetandyo Wignjosoebroto, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994. 321 Sayangnya, tak semua orang yang diberi kepercayaan untuk merumuskan hukum yang ideal menurut cita-cita pembangunan hukum nasional memahami keadaan itu. Keringnya akan pemahaman “mengerti sejarah” dan lunturnya semangat ke-Indonesiaan dengan pilihan ideologi Pancasilanya dan digantikan dengan sikap (yang kemudian menjadi pilihan politik hukum) pragmatis semakin mempercepat terwujudnya hukum (kasus undang-undang hak cipta nasional) yang tidak pernah berjalan secara simetris dengan masyarakatnya. Yang dalam bahasa penelitian disebutkan, validitasnya tertolak atau antara hukum yang dihasilkan dengan masyarakat yang akan diatur oleh hukum itu tidak memperlihatkan hubungan yang signifikan. Terjadi ketimpangan yang dahsyat antara das Sollen dengan dan Sein. Jika faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan itu hendak diurai satu persatu, maka pilihan pendekatan dengan menempatkan hukum sebagai satu sub sistem dalam sistem nasional, tak bisa tidak harus dilakukan. 236 Pada bahagian awal bab ini akan diuraikan tentang substansi hukum undang-undang hak cipta nasional. Gagasan-gagasan pembuat undang-undang akan dapat dicerna dalam substansi undang-undang tersebut, meliputi landasan ideal atau landasan filosofisnya, landasan juridis normatif atau konstitusional dan landasan politis atau landasan operasional. Apakah ketiga landasan ketatanegaraan ini cukup solid diakomodir oleh undang-undang hak cipta nasional itu. Uraian berikutnya adalah pada tataran struktur, apakah struktur lembaga pembuat undang-undang, lembaga penegak hukum dan struktur pemerintahan eksekutif berada pada koridornya masingmasing sebagai wujud dari sparation of power untuk menunjukkan ciriciri negara hukum. Atau justeru terjadi saling intervensi atau terjadi politik transaksional dalam pembuatan hukum ataupun dalam 236 Karena hanya dengan pendekatan yang demikianlah persoalan ketimpangan itu dapat diurai. Dengan pendekatan itu hukum tidak hanya dipandang sebagai gejala atau fenomena normatif, akan tetapi juga sebagai gejala atau fenomena sosial, ketika ditelusuri dari awal pembuatannya yang berpangkal pada perilaku orangorang yang duduk di lembaga pembuat undang-undang, ketika hukum itu diterapkan berpangkal pada perilaku aparat penegak hukum dan perilaku masyarakat sebagai pemegang peran yang dituju oleh kaedah hukum itu. Mau tidak mau pendekatan studi hukum empirik (non doktrinal riset), meliputi pendekatan politik hukum, sosiologi hukum dan antropologi hukum (untuk memahami budayai hukum) akan mewarnai uraiurai berikut ini. Begitulah cara kerja penelitian hukum, kata Satjipto Rahardjo 236 jika ingin memahami the full fenomena social reality of law. Pada bahagian inilah digunakan secara optimal data penelitian lapangan dengan pilihan metode non doktrinal riset. 322 penerapannya. Selanjutnya untuk menyempurnakan kajian terhadap pilihan politik hukum dengan kodifikasi parsial yang pragmatis dan penegakan hukumnya melalui pendekatan sistem hukum, pada bahagian ini uraian dilengkapi kajian mengenai kultur (budaya) hukum yang meliputi budaya; prilaku (budaya) legislatif, prilaku (budaya) aparatur penegak hukum dan prilaku (budaya) masyarakat. Uraian selanjutnya akan mengetengahkan pembahasan tentang dampak penegakan hukum hak cipta karya sinematografi terhadap industeri perfilman nasional. Entah itu pengaruh norma hukumnya atau karena pengaruh penegakan hukumnya yang lemah atau budaya hukum masyarakat Indonesia yang belum bisa mengapresiasi sebuah karya seni berupa karya sinematografi, hingga akhirnya dunia perfilman nasional bak kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Untuk menyahuti cita-cita kemerdekaan, tulisan ini diupayakan untuk merumuskan gagasan undang-undang hak cipta dan lembaga ketatanegaraan yang ideal bagi terwujudnya impian masyarakat adil dan makmur yang dapat merangsang pertumbuhan kreativitas pencipta dengan norma hukum yang think globally, commit nationally dan act locally. Selanjutnya bab ini akan ditutup dengan analisis dan temuan. B. Substansi Hukum Mengacu pada pandangan Friedman substansi hukum itu adalah materi-materi atau norma-norma yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan meminjam konsep Hart, 237 materi hukum dibaginya dalam dua kelompok yaitu : primery rules dan secondary rules. Pembagian menurut Hart adalah pembagian yang didasarkan pada kebutuhan hukum itu sendiri, yakni norma hukum yang mengatur masyarakat dan norma hukum tentang pelaksanaan dari norma hukum itu sendiri (peraturan organik). Menyimpang dari kerangka Hart, substansi hukum haruslah berisikan : 1. Pertimbangan-pertimbangan filosofis yang mengacu pada pandangan ideologis. 2. Pertimbangan-pertimbangan juridis 3. Pertimbangan-pertimbangan yang menjadi alasan politis 237 Aturan primer adalah peraturan-peraturan pokok yang digunakan H.L.A. Hart, Lebih lanjut lihat H.L.A. Hart, The Concept of Law, Clarendon Law Series, At The Clarendon Press, Oxford, New York, 1982. 323 Sebuah peraturan hukum yang tidak memenuhi dasar pertimbangan tersebut menurut ilmu perundang-undangan maka pemberlakuan hukum itu dapat ditolak atau tertolak dengan sendirinya. 238 Penolakan itu dapat dilakukan dengan menguji undang-undang yang dilahirkan itu apakah telah sesuai dengan dasar pertimbangan filosofis, juridis dan politis. Dalam kaitannya dengan penyusunan undangundang M. Solly Lubis 239 mengemukakan tiga landasan yang dapat dijadikan sebagai parameter, rujukan, acuan, kerangka berfikir dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yaitu yang disebutnya sebagai paradigma yang tak boleh ditinggalkan. Tiga paradigma itu adalah : 1. Paradigma filosofis atau landasan filosofis (filosofische grondslag) 2. Paradigma yuridis atau landasan yuridis (juridische grondslag) 3. Paradigma politis atau landasan politis (politische grondslag) 1. Paradigma Filosofis Konstruksi undang-undang hak cipta nasional yang berlaku hari ini adalah hasil rekonsfigurasi politik hukum melalui pilihan politik hukum konkordansi dan transplantasi yang pernah dilakukan selama kurun waktu hampir satu abad di kawasan nusantara. Dalam proses itu ada sejumlah nilai sosial dan kultural yang tak terkira jumlahnya yang hilang, terkikis ataupun terpendam. Dengan meminjam konsep geologi tentang proses peremajaan (rejuvenation) akan sangat mungkin terjadi proses penuaan terhadap nilai-nilai yang hilang itu dan menjadi manifest (muncul), lalu berubah menjadi sikap menetang, ketidak pedulian atau terang-terangan memberi perlawanan pada saat kaedah hukum hasil transplantasi itu diterapkan ketika terjadi stagnasi dalam proses penegakan hukum yang mengabaikan realitas. 240 238 Lebih lanjut lihat Sri Soemantri, Hak Menguji Materiil di Indonesia, Alumni, Bandung, 1977. 239 M. Solly Lubis, Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal. 15. 240 Perlawanan yang nyata untuk kasus di luar obyek studi ini lihatlah, ketika nilai-nilai yang terpendam (laten) itu kemudian muncul (manifes) ketika rakyat Aceh menentang dan melakukan gerakan perjuangan untuk keluar dari NKRI lalu dengan sebuah kompromi politik di Helsinky ditanda tangani sebuah kesepakatan bahwa Aceh diberi otonomi khusus untuk menjalankan Syari’at Islam, sebuah nilai yang dihilangkan dalam sejarah perjalanan masyarakat Aceh bergabung di bawah naungan NKRI. Lebih lanjut lihat Fikar W. Eda dan S. Satya Dharma, Sebuah Kesaksian Aceh Menggugat, 324 Para produsen karya sinematografi illegal dan para konsumen illegal, menjadi tidak peduli dengan kenyataan bahwa negeri ini memiliki undang-undang hak cipta, negeri ini memiliki kesepakatan dengan dunia internasional dan negeri ini mempunyai perangkat penegak hukum, serta negeri inipun memiliki lembaga peradilan yang siap menjatuhkan sanksi hukum. Memori sejarah politik hukum pembentukan undang-undang hak cipta nasional sering direntang terlalu pendek manakala hendak mengkonstruksikan undang-undang hak cipta yang baru, pemenggalanpemenggalan pengalaman masa lalu terus dilakukan dan rentang sejarah yang utuh cenderung diabaikan dan yang kemudian dimunculkan adalah kebutuhan sesaat dengan menimbang kenyataan hari ini yang menguntungkan hari ini. Pilihan politik hukum pembentukan undang-undang hak cipta nasional kemudian menjadi sangat pragmatis padahal semua mengetahui bahwa undang-undang hak cipta nasional dengan pilihan politik pragmatis itu tidak dapat ditegakkan. Berkali-kali alasan rendahnya sanksi hukum pidana dikemukakan sebagai alasan perubahan undang-undang hak cipta dari waktu ke waktu, akan tetapi setelah sanksi hukum pidana itu dinaikkan (diperberat) dalam undang-undang yang baru itu,perilaku pembajakan karya cipta sinematografi tidak pernah berhenti, alasan yang sama dikemukakan lagi (yakni ancaman hukuman masih terlalu rendah) untuk sekedar memberi jastifikasi guna perubahan kembali undangundang yang baru itu. Jika para politisi yang melibatkan diri dalam pembuatan undang-undang hak cipta nasional mau merentang tali sejarah, sebenarnya embrio undang-undang hak cipta nasional sudah mulai dikonstruksi sejak tahun 1912, pada saat Auteurswet 1912 Stb. No. 600 diberlakukan di wilayah nusantara. Pada saat itu pemberlakuan wet itu telah memperlihatkan suatu kenyataan bahwa kepatuhan masyarakat di wilayah Hindia Belanda terhadap wet itu ketika itu hampir dapat dikatakan tidak ada. Pada masa Kolonial Belanda itu, masyarakat di Hindia Belanda bisa dihitung jari yang mengetahui - dan bahkan untuk kelompok Bumi Putra tidak mengenal sama sekali – bahwa ada instrumen hukum yang memproteksi hak cipta. Apalagi dalam bidang karya sinematografi karena pada waktu itu film pertama sekali diproduksi di wilayah Hindia Belanda adalah pada tahun 1926. Teknologi pembajakan karya sinematografi pun belum dikenal pada Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999. Lihat juga Anthony Reid, Asal Mula Konflik Aceh, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005. 325 waktu itu. Sehingga dapat dipastikan tidak ada masyarakat Indonesia yang peduli dengan instrumen perlindungan hukum karya sinematografi pada waktu itu. Dalam bidang karya cipta lainnya seperti buku, pada masa itu dan sampai pada masa awal kemerdekaan pembajakan juga terus berlangsung. Artinya, kesadaran hukum masyarakat untuk penegakan hukum hak cipta pada waktu itu bukan tidak dimiliki, akan tetapi masyarakat tidak mengapresiasi undangundang itu karena secara sosiologis dan kultural proteksi hukum semacam itu tidak pernah dikenal dalam sejarah kehidupan mereka. Inilah tadi yang dikatakan bahwa pembelajaran sejarah dalam rentang pemberlakuan Auteurswet 1912 Stb. No. 600 tidak dijadikan dasar untuk rekonstruksi penyusunan undang-undang hak cipta nasional Indonesia pada saat dilahirkannya Undang-Undang Hak Cipta No.6 Tahun 1982, menggantikan wet itu. Ada memori sejarah yang dilupakan ketika undang-undang hak cipta nasional akan dilahirkan untuk menggantikan Auteurswet 1912 Stb. No. 600 dengan Undang-undang No. 6 Tahun 1982. Begitu juga ada memori sejarah yang dilupakan ketika Undang-undang No. 6 Tahun 1982 akan direvisi dengan konstruksi Undang-undang baru yang dituangkan dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1987. Demikian juga ada memori sejarah yang dilupakan ketika harus mengganti Undangundang No. 7 Tahun 1987 dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1997. Memori sejarah itupun dilupakan juga ketika menyusun Undangundang No. 19 Tahun 2002 menggantikan Undang-undang No. 12 Tahu 1997. Yang diingat adalah kebutuhan-kebutuhan sesaat yang mendesak untuk menjawab berbagai tekanan politik internasional hingga akhirnya yang terjadi adalah pilihan politik hukum yang pragmatis dan itu memberi warna dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002. Warna itu tidak hanya menyangkut warna normatif akan tetapi juga menyangkut nilai-nilai filosofis yang merupakan the original paradigmatic value of Indonesian culture and society yang terabstraksi dalam landasan ideologi bangsa dan negara yakni Pancasila. Landasan ideologi inilah kemudian dijadikan sebagai landasan politik hukum pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebuah ideologi adalah sebuah gagasan, sebuah idea, sebuah cita-cita, sebuah harapan yang diyakini oleh penganutnya sebagai suatu landasan kebenaran untuk mewujudkan cita-cita atau harapan tersebut. Berbeda dengan agama, ideologi oleh pencetusnya yakni Destutt de Tracy seorang pemikir Perancis yang pertama kali menggunakan istilah ideologi dalam bukunya, Elements d’ ideologie yang terbit tahun 1827 adalah sebuah kebenaran di luar otoritas agama. Konsep ini muncul 326 adalah proyek besar filsuf “Pencerahan” yang berusaha keras mensterilkan tubuh ilmu pengetahuan dari virus-virus prasangka agama, kepentingan pribadi dan kepercayaan mistik-metafisik dengan mengukuhkan metode ilmiah sebagai satu-satunya epistimologi yang sahih. Namun, setelah lebih dari satu abad berselang pasca de Tracy, ideologi tidak lagi bermakna tunggal. Karena tidak henti-hentinya dicermati dari pelbagai kerangka pemikiran dan sudut pandang, ideologi menjadi satu istilah penting dalam ranah ilmu sosial yang memiliki banyak tafsir. Muncullah kemudian pelbagai konsep ideologi dengan pendekatan, kekhasan dan ruang lingkup yang beragam. Tetapi, jika ideologi kita letakkan dalam kerangka umum, Microsoft Encarta Encylopedia (2003) akan menawarkan pada kita sebuah definisi yang tampaknya agak komprehensif, yakni suatu sistem kepercayaan yang memuat nilai-nilai dan ide-ide yang diorganisasi secara rapi sebagai basis filsafat, sains, program sosial ekonomi politik yang menjadi pandangan hidup, aturan berpikir, merasa, dan bertindak individu atau kelompok. 241 Pendekatan studi hukum sangat erat kaitannya dengan ideologi, karena hukum memuat cita-cita, harapan dan keinginan. Di Indonesia cita-cita dan keinginan itu dituangkan dalam pembukaan UUD 45. Itu jugalah alasannya, mengapa kemudian ideologi dijadikan sebagai landasan filosofis pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-undang tak boleh bertentangan dengan cita-cita negara, bermakna juga tak boleh bertentangan dengan ideologi bangsa. Ideologi akan selalu bersembunyi di balik atau di belakang tiap-tiap norma hukum atau undang-undang. Negara penganut ideologi komunis, dalam undang-undangnya akan tergambar nilai-nilai komunis (comunism values). Demikian juga negara penganut ideologi Islam, dalam undang-undangnya akan tercermin nilai-nilai Islam (Islamic values). Nilai-nilai hukum yang kapitalis tersembunyi di balik norma hukumnya, pastilah negara itu penganut ideologi kapitalis. Indonesia sebagai penganut ideologi Pancasila seyogyanya dalam undangundangnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ideologi Pancasila adalah ide dasar yang dijadikan sebagai pandangan hidup, cita-cita (ideal), basis visi dan missi dalam praktek kehidupan bernegara, termasuk dalam praktek perumusan cita-cita politik hukum nasional. Pilihan ideologi ini telah meleburkan kenyataan pluralisme hukum di Indonesia dalam tataran nilai. Sebenarnya ini adalah merupakan modal yang paling kuat bagi Indonesia untuk menyusun hukum nasionalnya termasuk undang- 241 Ian Adams, Ideologi Politik Mutakhir Konsep, Ragam, Kritik dan Masa Depannya, Qalam, Yogyakarta, 2004, hal. viii 327 undang hak cipta yang dapat diukir atau dilukiskan di atas “kain sutra” yang disepakati sebagai negara Indonesia. Namun sayangnya kemerdekaan yang oleh Bung Karno disebutnya sebagai “jembatan emas” dan dapat dijadikan sebagai pintu gerbang untuk menyeberang menuju cita-cita masyarakat adil dan makmur, tapi ternyata dalam perjalannya jembatan emas itu tidak dimaknai secara tepat. Hasilnya adalah hukum yang semestinya dapat ditorehkan di atas kain sutra, ternyata diberi bingkai dan landasan ideologi kapitalis. Akhirnya terjadilah hukum seperti kata pepatah : “Kain Sutra Bersulam Belacu” dan ideologi Pancasila tergerus dan bahkan terkikis di tangan anak bangsa sendiri. Pilihan politik transplantasi hukum asing ke dalam undangundang hak cipta nasional utamanya yang bersumber dari perjanjian Internasional, seharusnya dilakukan dengan penuh pertimbangan yang arif, dan perhitungan yang jauh ke depan. Pandangan ini didasarkan pada berbagai kasus yang menunjukkan bahwa instrumen hukum Internasional digunakan sebagai alat imperialis model baru, seperti yang diingatkan oleh Hikmahanto Juwono 242 sebagai berikut : Hukum Internasional, utamanya perjanjian internasional, digunakan oleh negara maju untuk ‘mengekang’ kebebasan dan kedaulatan Indonesia. Berbagai perjanjian internasional yang diikuti oleh Indonesia berdampak pada terbatasnya ruang gerak pemerintah dalam mengambil kebijakan. Bahkan kebijakan yang diambil dengan diikutinya perjanjian internasional yang ditandatangani diharapkan selaras dengan standar internasional. Indonesia terlalu takjub dengan tawaran-tawaran perdagangan bebas, pasar bebas, dan janji-janji bahwa, suatu saat Indonesia akan menjadi negara industri maju di kawasan asia, dan itu disikapi dengan menerima tawaran IMF dan World Bank untuk membiayai berbagaibagai proyek di Indonesia untuk pencapaian gagasan-gagasan kapitalisliberal itu. Puncaknya adalah ketika Indonesia meratifikasi GATT/WTO pada tahun 1994 dan di dalamnya memuat TRIPs Agreement, Indonesia kemudian disyaratkan untuk tunduk pada kesepakatan itu. Sebagai konsekuensi, Indonesia tidak hanya diharuskan untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan HKInya dengan TRIPs Agreement tetapi lebih jauh juga Indonesia harus mempersiapkan perangkat-perangkat hukum dalam negerinya untuk menegakkan instrument-instrumen hukum sebagai ikutan dari perjanjian internasional yang telah disepakati. Terdapat beberapa perjanjian internasional yang berlatarbelakang ideologi kapitalis yang 242 Hikmahanto Juwono, Op.Cit, hal 37. 328 oleh Pemerintah Indonesia tanpa merujuk pada perjalanan sejarah sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, Indonesia kemudian mengambil sikap dengan menyetujui instrumen hukum internasional mengenai perlindungan hak kekayaan intelektualnya. Kesepakatan-kesepakatan yang bersifat bilateral-pun dibangun dengan negara-negara tersebut yang antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut : 1. Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1988 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta atas Karya Rekaman Suara antara Negara Republik Indonesia dengan Masyarakat Eropa; 2. Keputusan Presiden RI No.25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat; 3. Keputusan Presiden RI No.38 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Australia; 4. Keputusan Presiden RI No.56 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Inggris; 5. Keputusan Presiden RI N0. 74 Tahun 2004 tentang Pengesahan WIPO Performances and Phonogram Treaty (WPPT); Belakangan ditambah lagi dengan pembuatan kesepakatan multilateral tentang perlindungan Audiovisual performances yang ditandatangani di Jenewa yang dikenal dengan Beijing Treaty on Audivisual Performance. 243 Pilihan-pilihan untuk menjalin kerjasama dalam perlindungan karya cipta dengan berbagai negara sayangnya tidak dilakukan dengan sebuah kesungguhan untuk melihat kembali latar belakang sejarah yang 243 Disebut sebagai Beijing Treaty karena kesepakatan itu lahir dari diplomatic conference yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2012 di Beijing yang juga sekaligus mengakhiri 12 tahun negosiasi multilateral di bawah WIPO. Indonesia menjadi negara ke-53 yang menandatangani Beijing Treaty ini, namun traktat ini belum diberlakukan menunggu ratifikasi paling sedikit 30 negara-negara anggota penandatangan. Lebih lanjut lihat PTRI Jenewa/EDPY, Indonesia Tandatangani Beijing Treaty on Audiovisual Performance di Jenewa, Rabu 19 Desember 2012. 329 telah mengabaikan berbagai nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat Indonesia. Negara Indonesia memanglah tergolong dalam negara yang masih berusia muda. Dalam usianya yang muda itu perjalanan sejarahnya telah mencatat bangsa ini dapat bertahan dan dipertahankan dengan nilai-nilai tradisional (nilai-nilai ke-Indonesiaan) yang dalam tulisan ini berkali-kali disebut sebagai the original paradigmatic value of Indonesian culture and society. Masuknya nilai-nilai baru meskipun pada tahap awal berjalan secara evolusi, akan tetapi pasca dihembuskannya issu globalisasi nilainilai baru itu masuk dengan gerakan yang lebih cepat. Peringatan Wertheim ketika menulis “Masyarakat Indonesia Dalam Transisi” menjadi relevan untuk dikutip dalam naskah ini. Wertheim menulis sebagaimana dikutip oleh Syamsuddin Ishak sebagai berikut : Proses yang terjadi pada masa lalu harus dipelajari dengan sangat sungguhsungguh. Bagaimanapun, proses itu bukanlah hukum yang dapat dilepaskan yang harus diterima secara pasif oleh umat mansia. Proses itu tidak lebih dari regularitas yang hanya berlaku dalam suatu pola masyarakat, pada suatu periode tertentu. Sejarah manusia merupakan suatu interaksi konstan dari pengulangan dan pembaruan, pengulangan yang bisa tampak dalam pakaian yang baru dan pembaruan yang tampak untuk suatu skema pengulangan. 244 Dalam siklus sejarah semacam itu relevan juga untuk dihubungkan dengan siklus politik hukum unifikasi dalam suasana pluralisme hukum di wilayah negara Hindia Belanda. 244 Syamsuddin Ishak, Keindonesiaan : Persatuan yang Terhenti, Kesatuan yang Asimetris, Prisma, Volume 30, 2011, LP3ES, Jakarta, 2011, hal. 4. Lihat lebih lanjut dalam Willem Frederik Wertheim, Masyarakat Indonesia dalam Transisi : Studi Perubahan Sosial, Penerjemah Misbah Zulfa Elizabeth, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1999, hal. xii. 330 Skema : 10 Siklus Politik Unifikasi Hukum Dalam Negara Hindia Belanda Hukum Eropa Hukum Hindia Belanda Hukum Pribumi Hukum Timur Asing Pada masa Hindia Belanda, ada keinginan agar di wilayah negara Hindia Belanda dapat diberlakukan hukum Eropa. Akan tetapi keinginan itu terus menerus mendapat perlawanan. Kenyataannya di Negara Hindia Belanda terdapat pluralisme hukum karena itu melalui Pasal 6 sampai 10 AB kemudian diteruskan dengan Pasal 75 RR lama diikuti dengan Pasal 75 RR baru terakhir disempurnakan dengan Pasal 131 dan Pasal 163 IS maka secara hukum telah dikukuhkan terdapat 3 golongan penduduk dengan 3 golongan hukum sebagaimana dalam gambar siklus di atas. Proses transformasi hukum Eropa agar dapat diterima menjadi hukum di wilayah Negara Hindia Belanda dilakukan dengan penerapan politik hukum dengan asas konkordansi yakni menyamakan berlakunya hukum di Kerajaan Belanda dengan di 331 wilayah Hindia Belanda. Politik hukum seterusnya dilakukan adalah setelah mendapat penolakan dari kalangan ahli hukum Bangsa Belanda sendiri yakni Van Vollenhoven untuk menggantikan hukum bumi putera dengan hukum Eropa kemudian dilaksanakan dengan pilihan politik hukum pernyataan berlaku, persamaan hak dan tunduk sukarela. Sampai akhirnya Indonesia merdeka, tak semua hukum Kerajaan Belanda itu dapat menggantikan posisi hukum Bumi Putera. Alasan yang sesungguhnya dapat dikemukakan adalah karena hukum bumi putera itu mempunyai “rohnya sendiri”, mempunyai spirit sendiri, mempunyai ideologi sendiri. Sampai setelah Indonesia merdeka-pun hukum asli bumi putera itu tetap tumbuh, hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia seperti hukum adat dan hukum agama. Mengapa kemudian Pemerintah Hindia Belanda menempatkan orang Jerman dan orang Jepang kedalam golongan hukum Eropa ? Padahal orang Jepang adalah orang Asia yang dapat dikategorikan sebagai golongan penduduk Timur Asing. Akan tetapi karena ini berkaitan dengan kepentingan dagang dan dagang mempunyai ideologi yang sama yakni kapitalis-liberal, maka orang Jepang pun dikelompokkan kedalam golongan hukum Eropa. Ini adalah sebuah pertanda bahwa ideologi begitu penting dalam pembentukan hukum. Siklus di bawah ini akan memperlihatkan bagaimana undangundang hak cipta nasional terbentuk dengan latar belakang ideologi yang berpangkal pada ideologi kapitalis. Sebuah ideologi yang menurut ramalan Bell dan Fukuyama sebagai ideologi akhir dari peradaban umat manusia yang oleh Ian Adam disebutnya sebagai Ideologi Pemenang. Dalam kaitannya dengan Undang-undang Hak Cipta, hubungan antara ideologi itu dapat dilihat dalam skema di bawah ini. 332 Skema: 11 Siklus Ideologi Pembentukan Undang-undang Hak Cipta Nasional Tekanan Amerika Negara Industri Maju (Ideologi Kapitalis) UU No. 7/1987 Ideologi Pancasila UU No. 6/1982 Auteurswet 1912 Stb No. 600 Bern Convention (Ideologi Kapitalis UU No. 12/1997 Undangundang Hak Cipta Nasional UU No. 19/2002 TRIPs Agreement diikuti dengan beberapa konvensi internasional (Ideologi Kapitalis) 333 Ketika Berne Convention telah ditanda tangani oleh sebagaian besar masyarakat Eropa, Belanda pada masa itu diharuskan menyesuaikan undang-undang hak cipta dengan konvensi itu. Segera setelah Belanda merevisi undang-undang hak ciptanya dengan Auteurswet Stb.1912 No. 600, beberapa waktu kemudian Negeri Kincir Angin itu meratifikasi Berne Convention. Selanjutnya dengan politik hukum kolonial, Kerajaan Belanda memberlakukan wet itu di wilayah jajahannya termasuk Indonesia yang kala itu menjadi bahagian dari Hindia Belanda. Berne Convention dengan latar belakang ideologi kapitalis itu masuk ke hukum Belanda yang juga penganut ideologi yang sama untuk selanjutnya menjalar ke wilayah hukum Hindia Belanda. Pasca kemerdekaan wet itu diteruskan dan menjadi acuan politik hukum nasional dalam penyusunan undang-undang hak cipta nasional, meskipun pada waktu itu ada keinginan murni untuk membangun hukum Indonesia dengan latar belakang ideologi Pancasila, sesuai dengan cita-cita kemerdekaan, sesuai dengan garis politik dan haluan negara, sesuai dengan jati diri bangsa yang disebut sebagai hukum kepribadian bangsa. Akan tetapi dalam kenyataannya, UU No.6 Tahun 1982, undang-undang hak cipta pertama yang menggantikan wet peninggalan Hindia Belanda tidak lebih dari translation atau terjemahan dari Wet yang berbahasa Belanda menjadi undang-undang yang berbahasa Indonesia. Singkatnya undang-undang itu tak dapat “meniupkan roh” Pancasila yang terjadi justeru sebaliknya undang-undang itu terjebak dalam lingkaran jiwa, nafas dan roh kapitalis. Masuk pada perjalanan berikutnya, ketika UU No.6 Tahun 1982 diberlakukan, ternyata di dunia, terutama di negara-negara industeri maju, terjadi perubahan besar pada peradaban umat manusia, ketika teknologi komunikasi, komputer dan teknologi serat optik ditemukan. Karya cipta sinematografi yang berasal dari negara asing itu menjadi industri kreatif yang tumbuh pesat yang banyak menyumbang pertumbuhan ekonomi negara-negara maju tersebut. Sementara di negara dunia ketiga termasuk Indonesia ketika itu, masih terbelakang dalam teknologi itu dan banyaklah kemudian terjadi pembajakan atau pelanggaran hak cipta. Ini kemudian membuat negara seperti Amerika menjadi berang, puncaknya negara itu kemudian meminta kepada Indonesia untuk merubah undang-undang hak cipta nasionalnya yang intinya dapat memberi perlindungan terhadap karya cipta mereka. Ini fase kedua masuknya ideologi kapitalis ke dalam undang-undang hak cipta nasional. Fase berikutnya terjadi pelembagaan secara normatif dan terstruktur dalam dunia Internasional, ketika Uruguay Round 334 diakhiri dengan persetujuan GATT /WTO pada tahun 1994 yang memasukkan issu Hak Kekayaan Intelektual yang kemudian terlembaga dalam TRIPs Agreement. Hasil akhir ini juga adalah merupakan puncak kemenangan negara-negara kapitalis melawan negara-negara dunia ketiga yang sejak awal begitu “alergi” dengan kapitalis yang sejak awal telah menolak memasukkan issu Hak Kekayaan Intelektual dalam GATT. Pelembagaan secara normatif ini adalah fase ketiga masuknya faham ideologi kapitalis ke dalam undangundang hak cipta nasional, dengan merubah UU hak Cipta No.7 tahun 1987 menjadi UU Hak Cipta No.12 Tahun 1997. Fase keempat adalah fase ujian, apakah undang-undang yang sudah sesuai dengan keinginan negara-negara kapitalis itu dapat efektif diberlakukan, ternyata jawabannya tidak. Situasi penegakan hukumnya tetap sama seperti pada masa pemberlakuan Auteurswet 1912 Stb. No. 600 pada masa Hindia Belanda. Akan tetapi ada ketidak percayaan negara-negara maju tersebut dengan kenyataan itu. Kenyataan hak cipta asing di lapangan karya sinematografi terus-menerus dibajak. Tudingan pemerintah asing tak dapat ditampik, akan tetapi Pemerintah Indonesia tidak kehilangan akal, perjanjian bilateral untuk saling melindungi karya cipta di bidang itupun dibuat. Entah itu untuk meyakinkkan negara-negara tersebut agar Indonesia dianggap negara yang taat hukum di mata mereka, entah itu sebuah basa-basi, tapi yang pasti setelah perjanjian bilateral itu ditanda tangani pembajakan hak cipta tak pernah berhenti. Negaranegara asing itu tak pernah tahu dan tak pernah ingin tahu faktor penyebabnya, yang mereka tahu sampai hari ini masih pada alasan yang dulu-dulu juga, yakni sanksi hukum terlalu rendah, pada hal ancaman hukumannya sudah 5 tahun dan denda 5 milyar, jumlah uang yang tak pernah dilihat oleh pedagang kaki lima penjual hasil karya sinematografi bajakan. Pembuat undang-undang di negeri inipun seolah-olah kehabisan kamus, diturunkan razia besar-besaran, tetapi setelah razia praktek pembajakan berjalan lagi. Anjing menggonggong kafilah lalu, biduk lalu kiambangpun bertaut. Tak ada yang istimewa dari gerakan razia yang dilakukan oleh aparat keamanan. Memang sulit untuk memberikan jawaban terhadap fenomena ini. Akan tetapi mengacu pada kerangkan Robert B.Seidman, akan diperoleh titik terang. Tidak mudah memberlakukan hukum nasional yang ditrasplantasi dari hukum asing. The law of nontransferability of law. Hukum suatu bangsa tak dapat diambil alih begitu saja tanpa mengambil seluruh pernak-pernik sosial budaya, kultur dan struktur yang mengitari tempat dimana hukum itu diberlakukan. Kulturnya adalah nilai (ide ologi) yang 335 terkandung dalam norma hukum itu sebagai pilihan sikap budaya (hukum) masyarakatnya. Strukturnya adalah, apakah aparat hukumnya sudah memiliki perilaku yang sama dengan aparat hukum tempat hukum itu berasal. Jika jawabnya tidak, maka itulah jawaban atas kegagalan penegakan hukum hak cipta di negeri ini. Jadi tak cukup transplantasi hukum itu, mencangkokkan norma hukumnya saja, tapi harus diikuti dengan struktur dan budayanya. Tampaknya transplantasi hukum Asing ke Undang-undang hak cipta Nasional masih akan menjalani masa sulit dalam penerapannya untuk tidak dikatakan gagal, sampai ada jawaban dari siapa pemenang Ideologi dalam pertarungan selanjutnya. 2. Paradigma Juridis Pekerjaan yang tersulit yang dihadapi dalam setiap kali praktek pembuatan peraturan perundang-undang adalah mensinkronkan peraturan yang akan dibuat itu dengan peraturan yang sudah menanti terlebih dahulu. Pertanyaan yang selalu dimunculkan adalah apakah peraturan perundang-undangan yang akan dibuat ini selaras atau justeru bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Harapan yang selalu diimpikan adalah peraturan yang dibuat itu haruslah selaras dengan peraturan yang sudah ada. Jika peraturan yang akan dibuat itu bertentangan secara ideologi dan normatif dengan peraturan yang sudah ada sebelumnya, maka ada dua alternatif yang harus ditempuh. Pertama, peraturan itu tidak jadi diteruskan pembuatannya, atau jika harus diteruskan peraturan yang sudah ada itu harus dengan tegas dinyatakan dicabut dalam peraturan perundangundangan yang baru itu. Bagaimana jika peraturan yang akan dibuat itu tetap diteruskan hingga menjadi peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, akan tetapi masih terdapat pertentangan secara ideologis dan normatif dengan peraturan yang sudah ada? Ada berbagai kemungkinan yang terjadi. Pertama, undangundang itu akan tertolak dalam pelaksanaannya di masyarakat. Kedua, undang-undang itu akan menjadi “macan kertas” alias tidak memiliki kekuatan yang secara kultural dan sosiologis tidak mengikat. Ketiga, jika harus dilaksanakannya, maka dalam penerapannya menjadi represif. Keempat, undang-undang itu akan kehilangan spirit atau “roh” sehingga terjadi pembiaran secara struktural. Kelima, akan terjadi konflik secara normatif (conflict of law). Keenam, undang-undang itu tak dapat mencapai tujuannya, apakah sebagai upaya untuk 336 mewujudkan keadilan atau kepastian hukum atau upaya untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Pada tahap awal yang perlu dicermati adalah sinkronisasi secara konseptual. Apakah konsep hak cipta karya sinematografi termasuk dalam kategori hukum benda? Jika ya, termasuk dalam klasifikasi benda berwujud atau tidak berwujud? Apakah juga penting untuk memberikan klasifikasi sebagai benda bergerak ? Kesamaan persepsi dalam memaknai konsep ini, tidak semata-mata dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kebutuhan belaka, akan tetapi harus dilihat dalam konteksnya dengan norma hukum lain yang sudah ada. Tentang perlindungan hak cipta karya sinematografi misalnya, ada dua konsep hukum yang penting yang harus dilihat dalam memaknai norma hukum yang berkaitan dengan itu. Konsep pertama adalah norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan menurut hukum pidana dan konsep kedua norma hukum perlindungan menurut hukum perdata. Klasifikasi normatif perlindungan hukum ini menjadi penting, manakala dihubungkan dengan pemahaman awam tentang pemaknaan konsep hak kekayaan intelektual. Masyarakat awam bahkan kaum intelektual tak sermuanya memahami konsep hak kekayaan intelektual, sehingga dalam praktek masih ditemukan pemahaman yang bias dan samar. Misalnya, kejahatan terhadap hak kekayaan intelektual itu, kejahatan terhadap jiwa atau kehormatan manusia atau kejahatan terhadap harta kekayaan, sebab frase “intelektual” melekat dengan manusia sebagai subyek. Berbeda dengan frase “hak milik atas tanah” atau “hak milik atas kenderaan bermotor” yang tidak melekatkan subyek dengan obyeknya dalam peristilahan itu. Untuk itu menjadi penting untuk mendudukkan kategori dan status hukum obyek yang diberi perlindungan oleh undang-undang hak cipta. Pemaknaan terhadap dua bentuk konsep perlindungan hukum ini, erat pula kaitannya dengan kedudukan obyek yang akan diberi perlindungan hukum itu, yakni karya cipta sinematografi. Sedangkan subyek yang akan diberi perlindungan adalah pencipta atau penerima hak. Oleh karena itu uraian berikut ini mengetengahkan pembahasan tentang kedudukan hak karya sinematografi dalam sistem hukum benda. Karya sinematografi adalah salah satu hasil karya yang dilindungi sebagai hak cipta. Hak cipta itu sendiri adalah merupakan hak kebendaan atau dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah "zakelijk recht". Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, memberikan rumusan tentang hak kebendaan yakni : hak mutlak atas suatu benda dimana 337 hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. 245 Rumusan bahwa hak kebendaan itu adalah hak mutlak yang juga berarti hak absolut yang dapat dipertentangkan atau dihadapkan dengan hak relatif, hak nisbi atau biasanya disebut juga persoonlijk atau hak perorangan. Hak yang disebut terakhir ini hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu, tidak terhadap semua orang seperti pada hak kebendaan. 246 Dalam praktek kelihatannya perbedaan antara hak kebendaan dengan hak perorangan kelihatannya tidak tajam lagi. Sebab dalam kenyataannya ada hak perorangan yang mempunyai sifat hak kebendaan. Hal ini dapat kita lihat sifat absolut terhadap hak sewa, yang dilindungi berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata dibandingkan dengan Auteurswet 1912 Stb. No. 600. Juga hak sewa ini mempunyai sifat mengikuti bendanya (droit de suit). Hak sewa itu akan terus mengikuti bendanya meskipun berpindahnya atau dijualnya barang yang disewa, perjanjian sewa tidak akan putus. Demikian juga halnya sifat droit de preference. Oleh Mariam Darus Badrulzaman 247, mengenai hak kebendaan ini dibaginya atas dua bagian, yaitu : Hak kebendaan yang sempurna dan hak kebendaan yang terbatas. Hak kebendaan yang sempurna adalah hak kebendaan yang memberikan kenikmatan yang sempurna (penuh) bagi si pemilik. Selanjutnya untuk hak yang demikin dinamakannya hak kemilikan. Sedangkan hak kebendaan terbatas adalah hak yang memberikan kenikmatan yang tidak penuh atas suatu benda. Jika dibandingkan 245 Sri Soedewi, Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata : Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal. 24. 246 Membedakan hak kebendaan dengan hak perorangan dengan : 1) Merupakan hak yang mutlak, dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. 2). Mempunyai zaaksgevolg atau droit de suite (hak yang mengikuti). Artinya hak itu terus mengikuti bendanya dimanapun juga (dalam tangan siapapun juga) benda itu berada. Hak itu terus saja mengikuti orang yang mempunyainya. ; 3). Sistem yang dianut dalam hak kebendaan dimana terhadap yang lebih dahulu terjadi mempunyai kedudukan dan tingkat yang lebih tinggi daripada yang terjadi kemudian. Misalnya, seorang eigenar menghipotikkan tanahnya, kemudian tanah tersebut juga diberikan kepada orang lain dengan hak memungut hasil, maka disini hak hipotik itu masih ada pada tanah yang dibebani hak memungut hasil itu. Dan mempunyai derajat dan tingkat yang lebih tinggi daripada hak memungut hasil yang baru terjadi kemudian. 4) Mempunyai sifat droit de preference (hak yang didahulukan). 5) Adanya apa yang dinamakan gugat kebendaan. 6) Kemungkinan untuk dapat memindahkan hak kebendaan itu dapat secara sepenuhnya dilakukan. Lebih lanjut lihat Sri Soedewi, Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata : Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal. 25-27. 247 Mariam Darus Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, BPHN - Alumni, Bandung, 1983, hal. 43. 338 dengan hak milik. Artinya hak kebendaan terbatas itu tidak penuh atau kurang sempurnanya jika dibandingkan dengan hak milik. Jadi jika disimpulkan pandangan Mariam Darus Badrulzaman di atas, maka yang dimaksudkan dengan hak kebendaan yang sempurna itu adalah hanya hak milik, sedangkan selebihnya termasuk dalam kategori hak kebendaan yang terbatas. Pandangan ini dapat disimpulkan dari rumusan pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2002 yang mengatakan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa hak cipta itu hanya dapat dimiliki oleh si pencipta atau si penerima hak. Hanya nama yang disebut sebagai pemegang hak eksklusif yang boleh menggunakan hak cipta dan selanjutnya dilindungi dalam penggunaan haknya terhadap subyek lain yang mengganggu atau yang menggunakan hak tersebut tidak dengan cara yang diperkenankan oleh aturan hukum. Dalam kaitannya dengan karya sinematografi, yang merupakan salah satu obyek yang dilindungi dengan hak cipta dapat dipastikan bahwa pencipta dan pemegang hak atas karya sinematografi adalah pemilih hak absolut dan orang yang mendapat ijin dari pencipta atau pemegang hak adalah pemegang hak relatif. Dalam karya sinematografi, terdapat banyak subyek hak cipta antara lain : 1. Penulis naskah (mungkin saja karya sinematografi itu diangkat dari novel). 2. Aktor atau para pemegang peran dalam cerita yang ditampilkan dalam karya sinematografi tersebut. 3. Produser yang membawahi semua urusan teknis yang berkaitan dengan pembuatan karya sinematografi tersebut (mulai dari juru kamera, juru lampu, penyusun skenario, penata suara, penata gambar sampai pada editor). 4. Pencipta lagu, penyanyi, arrangger musik (jika karya sinematografi itu menggunakan soundtrack lagu). Kesemua mereka ini adalah subyek-subyek yang sekaligus pemilik atau pemegang hak cipta secara bersama-sama atau juga secara sendiri-sendiri khusus untuk karya sinematografi yang menggunakan soundtrack lagu tanpa mengurangi hak cipta mereka-mereka yang terdapat dalam karya sinematografi tersebut. Karya sinematografi yang dalam Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 dirumuskan sebagai : ”media komunikasi massa 339 gambar gerak (moving images) antara lain meliputi : film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, di layar lebar atau ditayangkan di televisi atau di media lainnya. Karya serupa itu dibuat oleh perusahaan pembuat film, stasiun televisi atau perorangan”. 248 Karya sinematografi merupakan ekspresi/bentuk lahiriah dari sebuah ide atau gagasan awal yang bersumber dari berbagai pihak. Jika karya sinematografi itu berupa film cerita, maka gagasan itu bisa bermula dari karya cipta berupa novel. Selanjutnya jika karya sinematografi itu berupa film dokumenter, gagasan awal itu bisa berasal dari penulisan sejarah. Demikian juga jika yang ingin ditampilkan adalah berupa karya sinematografi dalam bentuk film iklan, gagasan itu bisa bersumber dari perusahaan yang akan mengiklankan produk-produknya. Prinsip perlindungan hak cipta dalam sinematografi adalah melindungi ekspresi dari ide atau gagasan dan bukanlah memberikan perlindungan pada ide atau gagasan itu sendiri. Ide atau gagasan itu sendiri tetap dilindungi sebagai hak cipta tetapi tidak sebagai hak cipta karya sinematografi, mungkin saja hak cipta dalam bidang karya novel, karya ilmu pengetahuan sejarah atau karya musik dan lagu. Selanjutnya bentuk/perwujudan dari sebuah ide atau gagasan itu dapat divisualisasikan dan kemudian direkam dengan menggunakan teknologi cakram optik yang kemudian terwujud dalam bentuk VCD ataupun DVD. Benda yang disebut terakhir ini adalah benda berwujud dan dilindungi sebagai hak kebendaan juga. Oleh karena itu, penempatan karya sinematografi sebagai bahagian dari hak cipta dan merupakan hak atas benda yang tidak berwujud dapat dilihat pada skema berikut ini : 248 Penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf k Undang-undang No. 19 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia tanggal 29 Juli 2002, Nomor 85 Tahun 2002 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220. 340 341 Dalam skema 249 di atas, kedudukan karya sinematografi dalam sistem hukum benda adalah termasuk dalam kategori atau kelompok benda tidak berwujud yang merupakan bahagian dari (komponen) hak cipta. Dengan menempatkan karya sinematografi sebagai benda tidak berwujud maka aspek perlindungan hukum terhadap benda ini tunduk pada sistem hukum benda tidak berwujud. Perlakuan dalam praktek penegakan hukumnya juga menjadi berbeda. Bukan benda materilnya seperti kepingan VCD atau DVD yang dilindungi, tetapi yang dilindungi adalah haknya yaitu : hak untuk memperbanyak atau hak untuk mengumumkan. Seseorang yang telah membeli VCD atau DVD, ia hanya dapat menikmati suara, gambar dan jalan cerita yang dapat ditampilkan dalam bentuk visual, akan tetapi ia tidak diperkenankan untuk memperbanyak kepingan VCD dan DVD tersebut atau menjualnya. Perbuatan memperbanyak atau memproduksi karya sinematografi tersebut itulah yang dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak (immateril) karya sinematografi yang dilindungi dengan hak cipta. Skema di atas juga menjelaskan adanya hubungan antara karya sinematografi dengan karya cipta lainnya. Termasuk juga hubungannya dengan hak terkait (neighbouring rights). Jika merujuk pada prinsip atau asas-asas yang dianut oleh Buku ke-II KUH Perdata yang menganut sistem tertutup, maka seyogyanya prinsip hukum perdata itu juga akan mengikuti tiap-tiap benda yang diatur di luar KUH Perdata termasuk hak cipta. Karena hukum perdata bidang hukum benda menganut prinsip tertutup maka hanya yang disebut dalam undang-undang secara tegas yang dapat dikategorikan sebagai benda. Di luar itu tidak dapat dikategorikan sebagai benda termasuk hak cipta, yang hanya menyebut sebanyak 12 (dua belas) item saja yang dilindungi sebagai hak cipta. Asas atau prinsip tertutup ini menyebabkan hak-hak yang dapat dilindungi 249 Skema di atas berbeda dengan pemahaman yang selama ini telah dikembangkan dalam berbagai literature yang menempatkan Trade Secrets, Unfair Competition dan Application of Origin serta Indication of Origin sebagai hak kekayaan perindustrian (Industrial Property Rights). Hak-hak yang disebutkan terakhir ini adalah merupakan hak yang memiliki hubungan dengan Industrial Property Rights. Obyek yang disebutkan terakhir ini tidak memperlihatkan adanya unsur hak kebendaan. Tidak ada hak yang perlu mendapat perlindungan dari ketiga item obyek yang disebut sebagai bahagian dari industrial property righs. Sebut saja misalnya Trade Secrets atau rahasia dagang, tidak begitu jelas hak apa yang akan dilindungi. Sesuatu yang dirahasiakan dalam aktivitas perdagangan, mungkin cara pembuatannya, komposisinya, mungkin juga cara pemasarannya dan lain-lain sebagainya yang penuh kerahasiaan. Tentu saja hal ini tidak menggambarkan adanya hak kebendaan yang dilindungi, karena itu tidak dapat diklasifikasikan kedalam obyek hak atas benda immateril atau obyek hak kekayaan intelektual. 342 dengan hak cipta menjadi terbatas secara limitatif. Oleh karena itu tidak semua kreativitas manusia yang dilahirkan dari sebuah gagasan atau ide berupa ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusasteraan dapat dilindungi dengan hak cipta. Itu adalah satu contoh kecil saja bagaimana cara mencari simpul sinkronisasi dalam penyusunan sebuah undang-undang. Singkronisasi semacam itulah yang tidak terjadi dalam penyusunan Undang-undang hak cipta nasional,250 sehingga menimbulkan kesan undang-undang itu disusun berdasarkan pesanan. Atau lebih dari sekedar pesanan, mungkin saja karena tekanan. 3. Paradigma Politis Seekor anjing kata Adam Smith, tak pernah secara sadar berbagi tulang dengan temannya. Karena itu seekor anjingpun tak pernah menyisihkan kelebihan tulang yang ia dapat hari ini untuk disimpan guna keperluan esok hari. Kesadaran (budaya) seperti itu hanya ada pada diri manusia. Akan tetapi jika “kesadaran untuk berbagi” secara kolektif dan kesadaran “untuk hari esok” tidak lagi dimiliki oleh manusia, maka cara pandangnya sama dengan seekor anjing yakni “penyelamatan dirinya hari ini. Jika ini terus berlangsung maka dengan meminjam perkataan Hobbes, manusia akan menjadi serigala diantara sesamanya. Puncaknya berujung pada pilihan pragmatis. Apakah pilihan ini berbahaya ? Buat bangsa yang besar seperti Indonesia pilihan pragmatis ini sangat berbahaya. Berbahaya bagi kelangsungan bangsa ini ke depan. Setelah lepas dari penjajahan secara fisik, pilihan politik pragmatis, praktek penjajahan digantikan oleh bangsa sendiri dengan sekutunya negara asing, namun bentuk penjajahannnya berubah menjadi penjajahan peradaban, penjajahan ideologi, penjajahan kultural, yang wujudnya adalah menerima apa adanya tekanan negara asing. Bagi segolongan elit politik, bersekutu dengan negara asing adalah menguntungkan. Lihatlah bagimana Soeharto berkuasa dan bertahan lebih dari tiga dasawarsa, karena berada di bawah bayang-bayang kekuasaan Amerika. Indonesia dijadikan Amerika sebagai boneka guna melawan ideologi dan negara Komuis . Pasca keruntuhan komunis, Amerika kemudian menjadi kekuatan tunggal satu-satunya di dunia. Agaknya sudah waktunya pula untuk tidak berlama-lama melindungi kekuasaan tirani di Indonesia. 250 Penempatan redaksi Pasal 2 Undang-undang Hak Cipta Nasional, yang membatasi hak atas benda apabila disewakan, membuktikan bahwa norma ini keluar dari sistem hukum benda. 343 Puncaknya Soeharto harus lengser, dan Amerika berada di balik semua peristiwa itu.251 Matrik 31 Perencanaan Pembangunan Era 1945-2025 Thn Tantangan Yang Dihadapi Falsafah, Arah dan Tujuan Pembangunan 1945 1949 Peperangan, Blokade Ekonomi dan Diplomasi Internasional 1950 1959 Ketidakstabil an politik dan keamanan terbengkalain ya perekonomia n Pancasila, Pengakuan Dunia atas Kedaulatan Negara Republik Indonesia dan Pembebasan Bangsa dari Berbagai Keterbelakanga n Pengembangan Pancasila di bidang ekonomi, pengembangan kelembagaan ekonomi sosial politik bangsa dan peningkatan kesejahteraan rakyat 1960 1965 Konflik ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya dalam kegotongroyo ngan Nasakom Pancasila yang dijabarkan dengan pola pikir Nasakom untuk mewujudkan sosialisme Indonesia dengan semangat berdikari Paradigma Strategi Kebijakan dan Program Pembangunan Membangun Demokrasi dan Kelembagaan Ekonomi serta Memperbesar dan Menyebarkan Kemakmuran Rakyat Secara Merata Kelembagaan Pemerintahan dan Perencanaan Sisem dan Proses Perencana an Sistem Pelaksanaan dan Hasil yang Dicapai Pergantian Pemerintahan dan Perintisan Lembaga Perencanaan Perintisan perencana an berbasis ilmu pengetahu an Normalisasi dan standarisasi pengelolaan anggaran, pengakuan dunia atas kemerdekaan Indonesia, dan membaiknya perekonomian Independensi dan antidependensi di bidang ekonomi, sosial dan politik Cepatnya pergantian cabinet dan inovasi kelembagaan perencanaan - Kepanitiaa n pada Kementeri an Perdagang an dan Industri - Dewan Perancang Negara dan biro perancang negara - Dewan perancang nasional Tidak ada pemisahan kekuasaan, penguatan lembaga perencanaan pembangunan Menguatn ya perencana an pembangu nan berbasis ilmu pengetahu an Perubahan sistem dan proses pengangaran, ketidakstabilan ekonomi, politik dan pemerintahan Perencana an sentralisti s, berwawas an jangka panjang, bersifat nasional dan semesta, tidak didukung kemampu an pembiaya an RPNSB I mengikuti tripola dan melalui anggaran pembangunan, pencetakan uang serta terealisasinya beberapa proyek Manipol-Usdek, etatisme ekonomi dan pembangunan bangsa 251 Lebih lanjut lihat Horst Henry Geerken, A Magic Gecko Peran Cia Di Balik Jatuhnya Soeharto, (Terjemahan Tingka Adiati), Kompas, Jakarta, 2011. 344 1966 1968 Tingginya inflasi, kemerosotan ekonomi dan hancurnya prasarana fisik dan kelembagaan Pengamalan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam berbagai bidang kehidupan Konsistensi dalam pengamalan Pancasila dan UUD 1945, rasional dan realistis dalam pengelolaan kebijakan, program dan anggaran Pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas yang sehat dan dinamis serta berkelanjutan Penataan kelembagaan pemerintahan dan perencanaan pembangunan berbasis ilmu pengetahuan Persiapan penyusun an rencana pembangu nan lima tahunan Persiapan membangun tata kelola pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungj awabkan. 1969 1994 Pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur ekonomi, pemerataan pembangunan dan persiapan tinggal landas Pancasila dengan titik berat pada pembangunan bidang ekonomi dan bidang-bidang lain bersifat menunjang dan melengkapi Stabilitas politik dan pemerintahan serta mantapnya lembaga perencanaan Pengelolaan secara terkendali, berkembangnya peran serta masyarakat, berorientasi kepada golongan ekonomi lemah Kemajuan, kemandirian dan keadilan melalui pembangunan manusia secara terpadu dengan pembangunan bidang lainnya yang berorientasi pada trilogy pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan Reformasi total, konsolidasi demokrasi, desentralisasi, akuntabilitas pemerintahan dan pembangunan berkualitas Upaya mewujudkan kesinambung an pembangunan Keterkaita n erat antara perencana an jangka panjang, menengah dan tahunan, keterkaita n antara pusat dan daerah serta antara perencana an dan pengangg aran Peningkat an partisipasi dan pemberda yaan masyarak at 1994 2019 Peningkatan, pembaruan dan perluasan bidang pembangunan Pancasila dan mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, adil dan sejahtera 1998 2004 Krisis multidimensi, demokratisasi , desentralisasi dan penegakan tata kelola pemerintahan yang baik Pancasila, masyarakat madani dan pemulihan ekonomi Penerapan prinsip good governance dalam manajemen pemerintahan, pengenalan eprocurement dan pulihnya perekonomian Pancasila dan pembangunan inklusif Pro-growth, propoor, pro-job dan pro-green Kabinet presidensial dalam sistem multipartai, pelembagaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pancasila, pembangunan Quality growth, creative and Cabinet presidensial Propenas sebagai penjabara n GBHN 1999 dan perubahan peran Bappenas dalam penyusun an anggaran Visi dan misi kepala pemerinta han terpilih dalam RPJMN/ D dengan pendekata n teknokrati s dan partisipati f Perencana an 2005 2009 Meningkatka n kualitas pertumbuhan dan desentralisasi dalam bingkai negara kesatuan RI 2010 - Reformasi birokrasi, Amandemen konstitusi, restrukturisasi kelembagaan negara dan reposisi peran Bappenas Upaya memenuhi kebutuhan public Meningkatnya transparansi dalam pelelangan/pen gadaan barang dan jasa pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi dan cukup tinggi Pengembangan wilayah pulau- 345 2015 percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, penegakan hukum dan peningkatan daya saing nasional yang berkualitas dan inklusif inclusive dengan sistem koalisi, meningkatnya aktivitas koordinasi perencanaan pembentukan komite ekonomi nasional dan komite inovasi nasional demokrati s dan teknokrati s pulau besar Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Sistem pelaksanaan dan hasil yang dicapai Hasil 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II Sumber : Mustopadidjaja AR, Bappenas Dalam Sejarah Perencanaan Pembangunan Indonesia 1945-2025, LP3ES, Jakarta, 2012. Matrik di atas memperlihatkan berbagai kebijakan pembangunan sejak masa awal kemerdekaan hingga hari ini. Pembangunan dalam bidang hukum hanya dijadikan sebagai instrumen atau alat pembangunan. Hukum tidak ditempatkan sebagai bidang (sektor) pembangunan sendiri, tapi ditumpangkan dalam pembangunan sosial budaya. Pembangunan sektor ekonomi secara terus menerus diprioritaskan. Keadaan ini sebenarnya tidak terlepas dari aturan yang memberi kewenangan kepada pemerintah eksekutif (Presiden) sebagai lembaga pemegang kekuasaan pembuat undang-undang, pada masa penyusunan Undang-undang hak cipta nasional ketika itu. Pasal 5 ayat (1) UUD 45 menyatakan “ Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” Ketentuan itu menempatkan presiden pada posisi pemegang kekuasaan legislasi, sedangkan DPR diposisikan sebagai pemegang kekuasaan legislasi yang semu. Presiden sebagai pimpinan eksekutif tertinggi yang semestinya menjalankan undang-undang, tapi justeru di tangannya berada posisi legislasi. Tak jarang pula undang-undang yang keluar pada masa itu, dalam berbagai pasalnya memberi peluang pula untuk pelaksanaan pasalnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Alhasil sempurna lah kewenangan legislatif dan kewenangan eksekutif berada di tangan satu orang yakni, Presiden. 252 252 Ketika Presiden ditetapkan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, tak pelak lagi presiden tampil bak penguasa Monarchi. Tampil berkuasa seperti seorang raja. Apa jadinya sebuah negara hukum dalam bentuk republik tapi dipimpin oleh seorang “raja”. Semua perintah adalah titah. Titah raja adalah hukum. Jika yang dititahkan pun salah tetap saja dipandang sebagai hukum. Dalam pepatah Melayu seorang yang bukan raja, tapi bertindak seolah-olah seorang raja, maka perilakunya akan “beraja di mata bertahta di hati”. Semua kebijakannya harus dipandang benar dan jika salahpun harus dibenarkan oleh para penggawa dan prajuritnya. Kenyataan ini berlangsung cukup lama di Republik ini. Itulah sebabnya berpuluh-puluh undang-undang pasca dibentuknya 346 Undang-undang Hak Cipta Nasional disusun dan dilahirkan pada priode UUD 45 belum diamandemen. Empat kali RRU hak cipta nasional semuanya diusulkan oleh Presiden (pemerintah) dan ketika itu Presiden juga memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Dalam bahasa yang agak ekstrim, UU hak cipta nasional yang ada dan pernah ada di Republik ini adalah undang-undang nya Presiden, karena itu yang tertangkap dalam undang-undang itu adalah sebagian besar aspirasi pemerintah, untuk tidak dikatakan kering dari aspirasi rakyat. Sekalipun selama priode Indonesia merdeka banyak juga undang-undang yang dilahirkan yang selaras dengan tujuan nasional, sekalipun undang-undang itu dilahirkan tidak karena aspirasi rakyat. Akan tetapi sebagian lagi undang-undang itu bertentangan dengan semangat kemerdekaan dan tujuan nasional. Undang-undang tentang Nasionalisasi Perusahaan Asing Belanda, UU No. 56 Tahun 1958 misalnya, adalah salah satu contoh saja untuk menyebutkan undangundang yang tidak aspiratif. 253 Matrik di bawah ini memperlihatkan kinerja lembaga pembuat undang-undang selama kurun waktu 1945-2012, akan tetapi tidak semua produk undang-undang yang dihasilkan dapat berterima di hati rakyat sehingga dikemudian hari dilakukan pengujian, seperti tergambar dalam matrik di bawah ini. Mahkamah Konstitusi yang harus dikoreksi kembali di mahkamah itu. Bung Karno pernah mengukuhkan dirinya sebagai presiden seumur hidup, Soeharto berkuasa lebih dari tiga dasawarsa yang mengukuhkannya sebagai “sang Raja” dengan berbagai julukan. Pasca reformasi, Habibi, Gus Dur dan Megawati, iklim demokrasi mulai terbuka, tapi perilaku monarchi tetap mewarnai jalannya pemerintahan dan semakin kental terasa pada era kepemimpinan Susilo Bambang Yoedoyono. Akan tetapi yang menarik adalah pasca amandemen UUD 45, kekuasaan legislasi beralih ke tangan DPR namun presiden memiliki hak untuk mengajukan RUU. Pasal 20 ayat (1) UUD hasil amandemen mengatakan “DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-undang”. Kemudian pada tahun 2011 keluar UU No.12 yang menegaskan bahwa dalam setiap rancangan peraturan yang diajukan harus disertai dengan Naskah Akademik. Lebih lanjut lihat David Jenkins, Soeharto & Barisan Jenderal Orba Rezim Militer Indonesia 1975-1983, Komunitas Bambu, Jakarta, 2010. Lihat juga Indriyanto Seno Adji, dan Juan Felix Tampubolon, Perkara H.M. Soeharto, Politisasi Hukum ?, Multi Media Metrie, Jakarta, 2001. 253 Undang-undang Pokok Agraria, Undang-undang Penanaman Modal Asing, Undang-undang Pertambangan, Undang-undang Kehutanan, Undang-undang Lingkungan Hidup, dan lain-lain. 347 Matrik 32 Kinerja Lembaga Pembuat Undang-undang (1945 – 2012) Periodisasi 1945-1949 (18 Agst 1945 – 14 Nop 1945) (14 Nop 1945 – 27 Des 1949) 1949-1950 27 Des 1949 – 1950 1950-1959 5 Juli 1959 1959-1966 1966-1971 1971-1977 1977-1982 1982-1987 1987-1992 1992-1997 1997-1999 1999-2004 2004-2009 2009-2010 * 2010-2011 * 2011-2012 * Kekuasaan Pembuat Undang-undang Jumlah Produk Undangundang Presiden BP KNIP 133 UU Presiden, DPR dan Senat 7 UU dan 30 UU Darurat Presiden dan DPR Presiden Presiden Presiden Presiden Presiden Presiden Presiden Presiden Presiden dan DPR Presiden dan DPR DPR DPR DPR 113 UU 10 UU 85 UU 43 UU 55 UU 46 UU 55 UU 70 UU 103 UU 174 UU 169 UU 16 UU 24 UU 30 UU 1163 UU Sumber : Pataniari Siahaan, Politik Hukum Pembentukan Undangundang Pasca Amandemen UUD 1945, Konstitusi Press, Jakarta, 2012 *Sumber : Harian Rakyat Merdeka, Mahfud : Pembuat UU Tidak Profesional, Kamis, 3 Januari 2013. Diolah kembali oleh : Saidin, 2013. 348 Matrik 33 Gugatan Uji Materil Terhadap Undang-undang di Mahkamah Konstitusi Tahun Jumlah Gugatan Kurun waktu 2011 169 Kurun waktu 2012 118 Jumlah 287 Sumber : Harian Rakyat Merdeka, Mahfud : Pembuat UU Tidak Profesional, Kamis, 3 Januari 2013. Jika dihubungkan kedua matrik di atas dapat disimpulkan bahwa, kinerja DPR dan Pemerintah dalam melahirkan Undang-undang memang terlihat nyata ada, akan tetapi hasil kerjanya di kemudian hari mendapat kecaman dari berbagai pihak hingga kemudian harus dilakukan uji materil. Selama kurun waktu tahun 2011 terdapat 169 undang-undang yang diajukan oleh berbagai kalangan untuk diuji dan selama kurun waktu 2012, terdapat 118 undang-undang yang daijukan untuk diuji secara materil. Catatan di Mahkamah Konstitusi dari 169 gugatan yang diajukan pada Tahun 2011, 97 gugatan diantaranya telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Diantara gugatan yang telah diputus itu terdapat 30 gugatan yang dikabulkan, 31 gugatan ditolak, 30 gugatan tidak dapat diterima dan 6 gugatan ditarik kembali seperti tertera pada matrik di bawah ini. Matrik 34 Tipologi Putusan Gugatan Uji Materil Terhadap Undang-undang Kurun Waktu 2011 Tipologi Jumlah Gugatan Persentase (%) Dikabulkan 30 30,93 Ditolak 31 31,95 Tidak dapat diterima 30 30,93 Ditarik kembali 6 6,19 Jumlah 97 100 % Sumber : Harian Rakyat Merdeka, Mahfud : Pembuat UU Tidak Profesional, Kamis, 3 Januari 2013. Diolah kembali oleh : Saidin, 2013. 349 Pada kurun waktu 2011 terdapat 30,93 % gugatan uji materil terhadap undang-undang yang putusannya dikabulkan dan itu berarti bahwa undang-undang yang diproduk itu mengandung cacat atau kekeliruan atau bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Pemerintah dan DPR tidak punya bukti yang kuat untuk mempertahankan keberadaan undang-undang itu. Alasan lain juga sering dijadikan sebagai dasar pertimbangan karena undang-undang itu tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Ini terjadi menurut Mahfud MD : “Karena kuatnya politik transaksional dalam bentuk tukar menukar kepentingan dalam pembentukan undang-undang”. 254 Ini memperlihatkan betapa lemahnya kader-kader politik yang duduk di lembaga legislatif. 255 Itulah sebuah kelemahan nyata dari pilihan politik hukum pragmatis. Undang-undang yang dihasilkan tidak dapat bertahan lama, bahkan mendapat perlawanan baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam. Ada kalanya juga undang-undang semacam itu terus dapat bertahan tapi tidak dapat mencapai tujuannya, alias “macan kertas”. Sebuah pertimbangan politis dalam penusunan undang-undang, bukanlah sebuah pertimbangan yang dilakukan hanya dimaksudkan untuk memenuhi unsur-unsur ilmu perundang-undangan atau sebagai syarat dalam legal drafting. Sebuah pertimbangan politis adalah sebuah dasar pijakan secara operasional, agar undang-undang yang akan dilahirkan itu adalah undang-undang yang menyahuti gagasan berdirinya negara, untuk mencapai tujuan negara dan yang lebih penting dapat dioperasionalkan. Undang-undang yang secara operasional dapat berjalan secara simetris dan simultan dalam satu bingkai negara guna menjawab seluruh ide dan cita-cita negara. Agaknya akan menjadi relevan mengaitkan cita-cita pembangunan hukum nasional dengan alasan politis yang dirumuskan sejak awal. Perumusan itu tidak dihadirkan secara “dadakan” pada saat persoalan itu tiba. Tugas pembuat undang-undang tidak hanya mengantisipasi setiap ada persoalan dalam masyarakt yang persoalan itu muncul tapi hukum yang mengaturnya belum ada, akan tetapi lebih dari sekedar itu yakni mendesain ke arah mana masyarakt ini akan di bawa dan hukum 254 Harian Rakyat Merdeka, Mahfud : Pembuat UU Tidak Profesional, Kamis, 3 Januari 2013. 255 Pada kesempatan lain Akbar Tanjung mengungkapkan lemahnya sistem pengkaderan di Parpol, melahirkan kader instan disampaikan pada acara “Dialog Membangun Budaya Demokrasi” diselenggarakan oleh Perhimpunan Pergerakan Indonesia, Jakarta, 8 November 2013, lihat Koran Sindu, Sabtu, 9 November 2013, hal. 9. 350 seperti apa yang akan dipersiapkan untukmengantisispasi masa depan itu. Karena itu pembangunan bidang hukum tidak bisa dilepaskan dengan pembangunan bidang sosial budaya, bidang pertahanan keamanan, bidang politik, ekonomi dan lain sebagainya. Demikian juga hukum atau undang-undang yang mengatur tentang Hak Cipta. Dalam hak cipta banyak terdapat kepentingan publik.256 Tidak hanya kepentingan para ilmuwan dan seniman (meliputi karya bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastera) yang terdapat dalam hak cipta, tetapi juga terdapat berbagai kepentingan kepentingan lainnya baik secara perorangan maupun kelembagaan. Semua itu harus mendapat tempat dalam perencanaan pembangunan hukum nasional yang dirumuskan sebagai wawasan politik hukum nasional yang dapat dituangkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), seperti gagasan M. Solly Lubis 257 sebab tanpa demikian, undang-undang yang dilahirkan akan keluar dari cita-cita hukum nasional. C. Struktur Hukum Secara etimologi struktur selalu diartikan sebagai susunan yang terdiri dari lapisan-lapisan, seumpama tulang ikan mulai dari kepala sampai ekor. Ada tulang utama yang besar, kemudian tulangtulang kecil yang panjang yang semakin bergerak ke ekor semakin kecil akan tetapi tetap tersusun secara rapi. Dalam satu organisasi sosial, struktur selalu bermakna susunan kepengurusan yang rapi, mulai dari jabatan yang paling tinggi sampai jabatan yang paling rendah. Dalam satu (organisasi) negara, struktur selalu dimaknai sebagai susunan badan-badan negara atau lembaga negara, mulai dari presiden sampai pada kepala lingkungan, mulai dari DPR sampai pada Lembaga Musyawarah Desa, mulai dari Mahkamah Agung sampai pada Pengadilan Negeri, mulai dari Jaksa Agung sampai pada Kejaksaan Negeri, mulai dari Kapolri sampai pada Kapolsek dan seterusnya. 258 Dalam struktur lapisan-lapisan itu akan bekerja secara profesional menurut tugas dan kewenangannya masing-masing, namun semuanya akan menyumbangkan (out put) untuk mewujudkan tujuan organisasi. Struktur dalam sistem sosial hanyalah sebuah komponen 256 Gillian Davies, Copyright and The Public Interest, Thomson Sweet & Maxwell, London, 2002. 257 M. Solly Lubis, Manajemen Strategis Pembangunan Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2011. 258 Lebih lanjut lihat, Inu Kencana Syafiie, Manajemen Pemerintahan, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2011. 351 saja dan tidak menutup kemungkinan struktur-struktur lain akan berada dalam satu sistem sosial itu. 259 Dalam berbagai studi ilmu sosial, struktur selalu bermakna sosiologis dan kulur selalu dimaknai secara antropologis. Teori-teori sosiologi tentang inipun sudah banyak dikaji oleh para sosiolog, sebut saja Durkheim, Spencer, Weber, Luhmann dan Giddens. 260 Pembahasan berikut ini tidak hendak mempertentangan berbagai pandangan dari kalangan sosiolog itu, tapi harus diakui inilah pembahasan yang paling sulit tentang hukum , jika hukum hendak ditempatkan dalam satu sistem yang keberadaannya didudukkan secara bersama-sama dengan sub sistem sosial lainnya dalam satu sistem sosial yang lebih luas. Sulit untuk memisahkan perilaku individu yang memiliki jabatan secara struktural dalam organisasi negara tapi kemudian pengaruhnya sedemikian besar dalam menentukan kebijakan negara . Lembaga kepresidenan misalnya yang dipimpin oleh presiden tidak hanya menjalankan tugas sebagai presiden menurut ketentuan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang ada, tapi tindakannya bisa berpangkal pada keinginan pribadinya atau tindakan secara individual yang ketika diaktualisasikan dianggap sebagai tindakan kelembagaan secara struktural kenegaraan. 261 Demikian juga dalam tatanan masyarakat dengan struktur masyarakat tradisional, ketika masyarakat “menghakimi” pencuri ayam dianggap sebagai tindakan yang sah karena budaya masyarakat melakukan eugenrichting (menghakimi sendiri) adalah sebuah tindakan yang lazim dalam struktur masyarakat (tradisional) atau ketika hukum dalam konsep struktur masyarakat modern tak mampu menjalankan 259 Lebih lanjut lihat, Nasikun, Sistem Sosial Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1987. 260 Lebih lanjut lihat Max Weber, Sosiologi, (Terjemahan Noorkholish), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009. Lihat juga Anthony Giddens, Kapitalisme dan Teori Sosial Modern Suatu Analisis Karya Tulis Marx, Durkheim dan Max Weber, UI Press, Jakarta, 2007. Lihat juga Peter Burke, Sejarah dan Teori Sosial, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011, hal. 163. 261 Sebagai contoh intervensi presiden terhadap kasus antara Kapolri dengan KPK, padahal sebenarnya yang disidik adalah oknum-oknum yang kebetulan bekerja di masing-masing institusi itu. Penyidik KPK yang bernama Novel sedang menyidik Perwira Tinggi Polri dalam kasus simulator SIM, Joko Sosesilo, tapi kemudian Novel pernah perkaranya dibekukan dalam kasus pembunuhan di Palembang, ketika yang bersangkutan menjabat sebagai Kapolres di salah satu wilayah hukum di Sumatera Selatan. Terlihat jelas intervensi “orang-orang” terhadap institusi, tapi kemudian berubah jadi kebijakan kelembagaan). 352 fungsinya, karena adanya perbedaan pada sistem hukum. Persinggungan antara struktur sosial pada masyarakat tradisional dan struktur sosial pada masyarakat modern tak bisa dihindari dan itulah yang di kemudian hari melahirkan kultur baru yang diikuti dengan kelahiran struktur sosial yang baru pila seperti yang digambarkan Kobben, ketika meneliti hukum pada level masyarakat desa di Suriname. Kobben 262 mengungkapkan : In the past the Djuka formed a state within the state, and in many respects this situation still holds. They still settle most of their disputes without referring to the Surinam authorities. Only for the most serious matters do they go to the police of their own accord. Usually it is the headman who does this. This happens in cases of murder or homicide and rape of a young girl – offenses that are rare. In the villages near the administrative centers, Mungo and Albina, however, it has become more and more usual in the last few years for young men who have taken a beating for seducing a woman to go to the police and complain. Two legal systems collide here. I try to explain that the police do not want people to take the law into their own hands, but I have little success. Da Jukun thinks he understands : “The police don’t think people ought to fight at all ; whoever fights is punished. So if a man seduces your wife you should put up with it. I suppose the wites don’t mind such things”. Penelitian Kobben membuktikan bahwa pada masyarakat Djuka di Suriname masih berlaku satu keadaan seperti di negaranya sendiri meskipun telah ada suatu otoritas negara yang disebut Suriname. Sebagian besar sengketa mereka tidak merujuk pada otoritas pemerintahan Suriname hanya dalam hal-hal kasus serius seperti pembunuhan, pemerkosaan atau pelanggaran-pelanggaran yang langka (yang tak pernah mereka kenal sebelumnya) barulah mereka merujuk polisi, itupun atas kemauan mereka sendiri. Di desa-desa dekat pusat pemerintahan seperti Mungo dan Aldina telah pula menggunakan lembaga kepolisian untuk menyampaikan keluhannya apabila ada seorang laki-laki yang memukul atau merayu mereka. Karena itu di Mungo terjadi dua sistem hukum dan itu dibiarkan hidup bahkan kadang-kadang kedua sistem hukum itu saling bertabrakan karena di satu sisi polisi ingin mengambil agar itu diselesaikan di tangan mereka sendiri. Siapa saja yang melakukan kekerasan, harus dihukum, akan tetapi Da Jukun (Lembaga Peradilan Tradisional Masyarakat Djuke) tidak keberatan jika langkah-langkah itu diambil oleh polisi. 262 Andre J.F. Kobben Law at the Village Level : The Cottica Djuka of Surinam, dalam Laura Nader (ed), Law in Culture and Society, University of California Press, London, 1997, hal. 127. 353 Disini terlihat bahwa dua sistem hukum, yang satunya tunduk pada sistem hukum lokal yang tradisional dan di lain pihak hukum pemerintah yang lebih modern juga diberlakukan. Keduanya dapat berjalan tanpa ada benturan yang berarti dalam aktivitas penegakan hukum dalam masyarakat Suriname, akan tetapi struktur lembaga penegakan hukum formal di Suriname berjalan tidak persis sama dengan ketentuan yang termuat dalam hukum formal. Ini juga yang terjadi di Indonesia dalam penyelesaian berbagai kasus-kasus pidana mulai dari pidana berat sampai dengan pidana ringan. 263 Penegakan hukum hak cipta yang tak kunjung membaik, juga dipengaruhi oleh derajat struktur lembaga penegak hukum yang belum tuntas dari pengaruh yang membebaskan mereka dari berbagai intervensi. Baik intervensi secara kelembagaan maupun yang datang dari perorangan. Derajat sistem soial itu sangat beragam, demikian Gaidens 264 dan makin beragam lagi jika dihubungkan dengan masyarakat yang plural yang dibedakan dalam ruang dan waktu. Katakanlah Indonesia sebagai sebuah sistem, yang disebut sebagai sistem (sosial) nasional yang luas. Tempat dan waktu yang berbeda menyebabkan keberterimaan akan satu aturan yang telah terkonsepkan secara struktural oleh badan negara yang memiliki kewenangan formal yang coba untuk diberlakukan secar unifikasi, memperlihatkan sikap (penerimaan) yang berbeda. Mungkin di Plaza atau di mall di Counter (outlet) dijual DVD dan VCD orginal dengan harga yang relatif lebih tinggi dan para konsumen tidak pernah ragu-ragu untuk mengeluarkan uanganya (mungkin dia juga tidak merasa bahawa tindaknnya itu merupakan wujud kepatuhannya terhadap UU hak Cipta) bila dibandingkan dengan konsumen yang membeli di gerai pedagang kaki lima oleh konsumen yang lain dengan harga relatif lebih murah (dan iapun tak pernah menyadari dia telah melanggar kaedah hukum UU Hak Cipta). 263 Praktek penyelesaian kasus pelanggaran lalu lintas dapat ditemukan setiap hari di jalan raya, sedangkan praktek penyelesaian kasus pidana besar, dapat dilihat dari peanaganan kasus pendompleng dana BLBI yang sebahagian besar tak pernah sampai ke pengadilan, lihat juga penangan kasus Bank Century yang tak kunjung usai, kasus yang melibatkan Andi Malarangeng dan Anan Urbaningrum yang terkesan lamban samapai pada lihat hasil akhir penyelesaian kasus Soeharto, Lebih lanjut lihat David Jenkins, Soeharto & Barisan Jenderal Orba Rezim Militer Indonesia 1975-1983, Komunitas Bambu, Jakarta, 2010. 264 Anthony Giddens, The Constitution of Society Teori Strukturasi Untuk Analisis Sosial, (Terjemahan : Drs. Adi Loka Sujono), Pedati, Pasuruan, 2003, hal. 200. 354 Kasus di atas menunjukkan sikap keberterimaan yang berbeda untuk kaedah hukum yang sama, hanya karena berbedanya ruang tempat, padahal di Maal itu juga dijual DVD dan VCD hasil pelanggaran hak cipta, akan tetapi para konsumen pikirannya telah terkoptasi bahwa di Mall akan ada jaminan bahwa barang yang dijual itu adalah barang yang original. Dalam kesempatan berkeliling di Eropa, guna melengkapi studi ini, tiap kali berhenti di kota-kota di Eropa, kami menyempatkan diri melakukan observasi di counter-counter penjualan DVD dab VCD hasil karya sinematografi. Kami memperoleh gambaran bahwa di ciunter-counter penjualan DVD dan VCD hasil karya sinematografi, tidak ditemukan barang illegal atau hasil pelanggaran hak cipta. Semua barang dijual dengan harga berkisar 7 sampai dengan 15 Euro per keping. 265 Apakah di negara-negara Eropa itu tidak ada pembajakan hak cipta karya sinematografi ? Sebuah wawancara non terstruktur yang kami lakukan dengan salah seorang warga negara Belanda 266 mengatakan : Saya sudah 40 tahun lebih di Belanda dan saya penggemar film. Sampai hari ini tidak kurang dari 500 keping VCD dan DVD di rumah saya dengan berbagai judul cerita, mulai film Jepang, Amerika, Prancis, India sampai film Indonesia. Film-film itu ada yang saya beli di Indonesia. Film-filmyang saya beli di Belanda dan di negara-negara Eropa lainnya, semuanya original dan saya beli dengan harga yang normal. Berbeda ketika saya membeli di Indonesia, saya mendapatkan harga yang murah, tapi kualitasnya kurang bagus, mungkin itu hasil bajakan. Di Belanda tidak ada dijual hasil bajakan, semua yang dijual legal yang ditandai dari lebel produksi dan lebel dari kantor pajak (cukai). Kondisi di Perancis berbeda dengan di Belanda. Dalam sebuah wawancara dengan seorang warga Perancis, 267 yang kebetulan selama 1 tahun tinggal di rumah kami, dalam wawancara dengan beliau, ia katakan : 265 Harga rata-rata perkeping berkisara Rp.75.000,- sampai dengan Rp.250.000,-Observasi ini kami lakukan di Belanda, Belgia, Itali, Spanyol, Swiss dan Jerman. Observasi didampingi oleh Co-Promotor Tan Kamello, pada bulan April 2012. 266 Wawancara dengan ABDUL KARIM BASHEL, No. Pasport : NVK 5 J 98 F 6, Alamat : Boris Pasternak Straat No. 469, Amsterdam – Holland, tanggal 26 Juni 2013, di Medan, pukul 15.00 Wib. 267 Wawancara dengan PAULINE SALEUR No. Pasport : 11CX64404, Kebangsaan : Perancis, Alamat 12 RUE CHARLES DE FOUCAULT 18390 SAINT GARMAIN DU PUY, FRANCE, tanggal 21 Juni 2013 di Medan, pukul 13.00 Wib. 355 Di Perancis tidak ada dijual DVD dan VCD bajakan seperti di Medan. Di Medan di mana-mana tempat ditemukan penjual DVD dan VCD bajakan. Di Pernacsis selain hukum tentang pelaku pembajakan itu ketat, juga orang-orang tidak banyak membeli VCD dan DVD, hanya kalangan orang-orang tua saja. Para anak muda lebih banyak mendownload di internet di situs-situs resmi dan tidak resmi. Mendownload di situs tidak resmi, juga tidak boleh itu melanggar hukum, tapi sulit ditelusuri pelakuknya, karena situs itu berganti-ganti nama, satu minggu sudah hilang, setelah itu ganti lagi. Selanjutnya, dalam sebuah wawancara dengan seorang warga Turki 268 yang kami lakukan, beliau mengatakan : Saya adalah penggemar film. Banyak VCD dan DVD di rumah saya dengan berbagai judul cerita, mulai film Jepang, Amerika, Prancis, India sampai film Indonesia. Film-film itu ada yang saya beli di Indonesia. Film-film yang saya beli di Turki dan di negara-negara Eropa lainnya, semuanya original dan saya beli dengan harga yang normal. Berbeda ketika saya membeli di Indonesia, saya mendapatkan harga yang murah, tapi kualitasnya tidak bagus, mungkin itu hasil bajakan. Di Belanda tidak ada dijual hasil bajakan, semua yang dijual legal yang ditandai dari label produksi dan label dari kantor pajak (cukai). Merujuk pada tiga wawancara dengan tempat yang berbeda, ternyata ditemukan perilaku yang bervariasi. Itu menunjukkan bahwa dalam sistem sosial, struktur mayarakat yang sama karena tempat dan waktu yang berbeda, perilaku hukum menjadi bervariasi. Model pembajakan bergeser ketika ditemukannya teknologi internet. Karena itu pilihan politik hukum harus juga dan mau tidak mau harus mengikuti trend perkembangan teknologi. Struktur sosial yang berubah pada akhirnya memaksa hukum untuk mengikuti perubahan itu. Pertanyaan berikutnya: apakah dengan perubahan sosial itu yang diikuti dengan perubahan hukum secara normatif, nilai juga ikut berubah ? Atau yang berubah normanya saja, dan nilai tidak iokut berubah ? Kasus UU hak cipta nasional, memeperlihatkan keduanya berubah, nilai dan norma ikut berubah. Ternyata tujuan negara tidak dapat dicapai melalui kerja-kerja individu. Tujuan negara sebagai suatu organisasi pemerintahan modern tunduk pada struktur organisasi yang dibakukan dalam hukum dasar yang dipilih sebagai dasar berpijak bangunan negara. Dalam konteks ketatanegaraan, badan-badan negara dibentuk sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan negara tersebut dan itu ditetapkan dalam kaedah hukum yang disebut sebagai hukum tata negara. Apa yang menjadi 268 Wawancara dengan Ali Cetin, warga negara Turki, tanggal 24 Juni 2013, di Medan, pukul 13.00 Wib. 356 fungsi badan-badan negara, bagaimana bentuk struktur organisasinya, bagaimana sistem pemerintahan yang dipilih dan lain sebagainya ditetapkan dalam kaedah hukum tata negara. Selanjutnya bagaimana badan-badan negara itu menjalankan fungsinya dalam struktur organisasi negara itu, hal itu diatur dalam hukum administrasi negara. Dalam praktek penegakan hukum, tidaklah cukup struktur yang dimaksudkan adalah struktur lembaga penegak hukum tetapi juga struktur lembaga pembuat undang-undang, struktur pemerintahan dan bahkan struktur masyarakatnya sendiri. Mengenai struktur masyarakat akan dibahas secara tersendiri dalam konteks budaya hukum. Organorgan negara seperti lembaga kepresidenan, lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, lembaga penegak hukum yang meliputi : kepolisian, kejaksaan dan kehakiman akan membawa pengaruh pada praktek penegakan hukum dalam kaitannya dengan struktur negara. Praktek-praktek transaksional dalam pembuatan undang-undang antara pihak eksekutif dengan pihak legislatif menjadikan produk undangundang itu gagal menyahuti aspirasi masyarakat. Demikian pula praktek transaksional dalam proses penegakan hukum (law enforcement) menyebabkan pula kaedah hukum itu gagal ditegakkan atau setidak-tidaknya gagal mencapai tujuannya. Uraian berikut ini, selain mengetengahkan tentang kinerja lembaga pembuat undangundang lebih jauh juga akan mengetengahkan uraian tentang lembaga penegak hukum dan lembaga pemerintah (eksekutif) dalam kaitannya dengan struktur dalam sistem hukum. 1. Lembaga Pembuat UU (Legislatif) Dalam konteks negara hukum, kekuasaan legislatif dapat dikatakan mendominasi semua proses politik. Semua kebijakan negara yang akan dituangkan dalam undang-undang berada di tangan lembaga legislatif. Proses politik pembentukan hukum oleh legislatif lebih superior dari lembaga manapun dalam sebuah negara hukum. Legislatiflah sebenarnya penentu arah dan kebijakan negara, eksekutif hanya menjalankannya saja, sedangkan judikatif lebih pada aspek mengawasi ; apakah sebuah undang-undang telah dijalankan dengan baik. Bahkan dalam kasus Indonesia legislatifpun menjalankan fungsi pengawasan. Begitu tinggi kedudukan politis lembaga legislatif. Meskipun dalam Undang-undang Dasar 1945 (sebelum di amandemen) kekuasaan pembentukan undang-undang pernah diberikan kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat hanya diberikan kewenangan untuk menyetujui. Pasca amandemen UUD 1945 kewenangan itu sudah 357 dialihkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, akan tetapi presiden dapat mengajukan usulan rancangan undang-undang. 269 Anggota legislatif sebenarnya adalah representatif dari rakyat Indonesia dari berbagai aliran politik, dengan segala tingkat kemajemukan kulturnya. Sebagai lembaga perwakilan yang memegang peranan “superior” itu, maka berbagai keinginan rakyat yang plural itu akan dibahas di dalam satu atap yang disebut Lembaga Perwakilan Rakyat. Di sana duduk perwakilan rakyat dari seluruh wilayah Indonesia mulai dari yang mewakili daerah sampai dengan yang mewakili kelompok agama (karena partai-partai juga dibentuk atas dasar itu), mulai dari daerah Aceh, Riau, Banten, Yogayakarta, Bali, sampai dengan Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Ketika ada satu tema undang-undang akan dilahirkan, tak terbayangkan hukum seperti apa yang harus dilahirkan untuk mengatur kepentingan masyarakat yang plural itu. Entah apa juga bentuk perdebatan di gedung legislatif itu, hingga muncul satu undang-undang yang yang kemudian disetujui dan akhirnya diterima sebagai undang-undang untuk mengatur masyarakat Indonesia yang plural itu. Tidak menjadi soal juga jika di kemudian hari produk undang-undang itu tidak “menyumbangkan” apa pun bagi tercapainya cita-cita hukum yang dapat menyahuti cita-cita kemerdekaan. 270 Kebijakan politik legislasi nasional yang demikian tak terelakkan lagi, karena Indonesia tidak memiliki pilihan lain ketergantungan Indonesia secara ekonomis (berupa pinjaman) dengan lembaga-lembaga keuangan Internasional, seperti International Monettary Fund (IMF), World Bank dan Asian Development Bank (ADB) dan bentuk ketergantungan lain adalah dengan perusahaan multisional. Perusahaan multinasional dapat mengeluarkan ancaman, akan hengkang dari Indonesia, jika negeri ini tidak merevisi atau 269 Lihat lebih lanjut Pataniari Siahaan, Politik Hukum Pembentukan Undangundang Pasca Amandemen UUD 1945, Konstitusi Press, Jakarta, 2012. 270 Lihatlah lebih lanjut produk UU No,5 Tahun 1960 Tentang UU Pokok Agraria, Undang-undang Pendidikan Nasional dan Peraturan Pelaksanaannya,..Tak ada juga yang peduli jika sebahagian masyarakat merasa mendapat perlakuan yang adil dan sebahagian lagi merasa mendapat perlakuan tidak adil, atau sebahagian masyarakat menjadi makmur dan sebagaian lagi menjadi miskin, atau sebahagian masyarakat menjadi cerdas karena mendapat kesempatan pendidikan sebagian lagi menjadi bodoh karena tak mendapat kesempatan bersekolah, karena produk undang-undang itu.Undangundang pada tatanan nasional, diproduk untuk menyahuti kepentingan elit politik dan elit penguasa, karena itu undang-undang yang lahir cenderung mewakili “Senayan-Jakarta” dan bagaimanapun juga produk hukum semacam itu tidak mapu mampu menyahuti kepentingan seluruh masyarakat Indonesia yang plural. 358 mereformasi aturan perundang-undangannya menurut standar yang mereka kehendaki. Ketergantungan ini menurut Hikmahanto Juwono 271 sering menjadi alasan intervensi Asing dalam proses legislasi Nasional, sekalipun intervensi semacam itu tidak dilarang oleh undang-undang, dalam arti tidak melanggar kaedah hukum Internasional. Akan tetapi ketergantungan semacam itu membuat Indonesia “terpaksa” menyetujui beberapa instrumen hukum Internasional, harus ikut menjadi anggota konvensi Internasional yang memiliki keterkaitan dengan ketergantungan itu. Atau setidak-tidaknya membuat perjanjian bilateral. Dengan perjanjian itu negara maju menjadi leluasa untuk melakukan intervensi dalam proses legislasi nasional di negara-negara berkembang seperti Indonesia dengan memanfaatkan prosedur hukum yang disepakati bersama. Meminjam istilah Hikmahanto, Instrumen hukum (perjanjian) Internasional itu dijadikan sebagai alat intervensi negara maju terhadap negara berkembang dalam proses legislasi. Paling tidak ada dua sasaran yang ingin dicapai. Pertama, negara berkembang tidak akan membuat hukum (undang-undang) yang tidak sesuai dengan hukum dari negara maju. Kedua, kepentingan Negara maju bisa “dipaksakan” tanpa harus dianggap melakukan intervensi urusan dalam negeri suatu negara. Negara maju sendiri, tidak berkepentingan untuk merubah hukum di negaranya, sebab hukum merekalah yang sejak awal menjadi rujukan perjanjian Internasional itu. Inilah yang terjadi untuk kasus Indonesia, ketika Indonesia ikut meratifikasi hasil putusan WTO/GATT dan Perjanjian Internasional ikutannya seperti TRIPs. Dampaknya Indonesia dengan segala keterbatasannya harus mengikuti amaran kesepakatan itu – karena itu telah menjadi kewajiban – yakni merevisi, mereformasi, menyesuaikan atau memperbaharui peraturan perundangundangan HKI nya. Itu adalah sebuah intervensi politik internasional yang nyata, intervensi politik negara-negara maju terhadap negaranegara berkembang. Reformasi Peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual setelah ratifikasi GATT/WTO janganlah dilihat sebagai persoalan intervensi biasa, akan tetapi harus dimaknai sebagai proses intervensi negara maju terhadap negara berkembang dan negara berkembang “terpaksa” melakukannya melalui pilihan politik 271 Lebih lanjut lihat Hikmahanto Juwono, Orasi Ilmiah, Hukum Sebagai Instrumrn Politik : Intervensi Atas Kedaulatan Dalam Proses Legislasi di Indonesia, Disampaikan pada Dies Natalis Fakutas Hukum USU ke-50, Medan, 12 Januari, 2004, hal.12. 359 pragmatis dan untuk kasus Indonesia diikuti dengan kebijakan transplantasi hukum.272 Perubahan peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia termasuk di dalamnya UU Hak Cipta, adalah keharusan yang lahir dari keterikatan secara hukum dan moral negara Indonesia atas keanggotaannya dalam organisasi perdagangan dunia tersebut. Sekalipun kebutuhan dalam negeri atau masyarakat Indonesia pada waktu itu memang belum mendesak untuk segera melakukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual tersebut. Bahwa arus globalisasi merupakan gelombang yang tak dapat dihindari sebagai kemajuan peradaban umat manusia yang diikuti dengan perubahan sosial hal itu sulit untuk disangkal. Akan tetapi mengikuti saja arus perubahan itu tanpa upaya untuk “menyaring” bahagian-bahagian perubahan yang mesti diikuti adalah suatu tindakan atau pilihan politik yang kurang arif. Pemerintah (Pusat) memang harus melakukan langkah-langkah politik yang strategis untuk menghadapi tuntutan negara maju, akan tetapi rakyat (daerah) jangan dikorbankan. Di sinilah perlunya wacana untuk menentukan bentuk struktur pemerintahan negara yang tepat. Hikmahanto 273 dalam pidatonya mengatakan : Sulitnya penegakan hukum di Indonesia berawal dari peraturan perundangundangan itu dibuat, paling tidak itu didasarkan pada dua alasan ; Pertama, pembuat peraturan perundang-undangan tidak memberi perhatian yang cukup apakah aturan yang dibuat nantinya bisa dijalankan atau tidak. Pembuat peraturan perundang-undangan sadar ataupun tidak telah mengambil asumsi aturan yang dibuat akan dengan sendirinya dapat berjalan. Di tingkat nasional, misalnya, UU dibuat tanpa memperhatikan adanya jurang untuk melaksanakan UU antara satu daerah dengan daerah lain. Kerap UU dibuat dengan merujuk pada kondisi penegakan hukum di Jakarta atau kota besar. Konsekuensinya UU demikian tidak dapat ditegakkan di kebanyakan daerah di Indonesia dan bahkan menjadi UU mati. Keadaan diperparah karena dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tidak diperhatikan infrastruktur hukum yang berbeda di berbagai wilayah di Indonesia. Padahal infrastruktur hukum dalam penegakan hukum sangat penting. Tanpa infrastruktur hukum yang memadai tidak mungkin peraturan 272 Pilihan pragmatis itu dilakukan, karena pihak negara maju selalu menjadi sumber ketergantungan negara berkembang baik ketergantungan secara ekonomi, politik maupun ketergantungan dari aspek keamanan, lebih lanjut lihat Sritua Arief & Adi Sasono, Indonesia Ketergantungan dan Keterbelakangan, Mizan, Jakarta, 2013. 273 lihat pidato, Hikmahato Juwono, Penegakan Hukum Dalam Kajian Law and Development: Problem dan Fundamental Bagi Solusi di Indonesia, Disampaikan pada acara Dies Natalis ke 56 Universitas Indonesia, Kampus UI Depok, Februari 2006, hal 13. 360 perundang-undangan ditegakkan seperti yang diharapkan oleh pembuat peraturan perundang-undangan. Kedua, peraturan perundang-undangan kerap dibuat secara tidak realistis. Ini terjadi terhadap pembuatan peraturan perundang-undangan yang merupakan pesanan dari elit politik, negara asing maupun lembaga keuangan internasional. Disini peraturan perundang-undangan dianggap sebagai komoditas. Elit politik dapat menentukan agar suatu peraturan perundang-undangan dibuat, bukan karena kebutuhan masyarakat melainkan agar Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang sebanding (comparable) dengan negara industri. Sementara negara asing ataupun lembaga keuangan internasional dapat meminta Indonesia membuat peraturan perundangundangan tertentu sebagai syarat Indonesia mendapatkan pinjaman atau hibah luar negeri. Peraturan perundang-undangan yang menjadi komoditas biasanya kurang memperhatikan isu penegakan hukum. Sepanjang trade off dari pembuatan peraturan perundang-undangan telah didapat maka penegakan hukum bukan hal penting. Bahkan peraturan perundang-undangan seperti ini tidak realistis untuk ditegakkan karena dibuat dengan cara mengadopsi langsung peraturan perundang-undangan dari negara lain yang notabene memiliki infrastruktur hukum yang jauh berbeda dengan Indonesia. Dua alasan di atas mengindikasikan peraturan perundang-undangan sejak awal dilahirkan tanpa ada keinginan kuat untuk dapat ditegakkan dan karenanya hanya memiliki makna simbolik (symbolic meaning). Dalam pidatonya yang lain Hikmahanto274 mengisaratkan betapa selama ini kebijakan pemerintah pusat dalam perubahan undang-undang hanya menguntungkan pihak asing, mulai dari perubahan UU HKI sampai dengan perubahan UU Kepailitan. Demikian juga ratifikasi konvensi Internasional, lebih daripada tindakan kamuflase agar Indonesia dipandang oleh negara-negara maju sebagai negara yang turut berperan aktif dalam menyongsong liberalisasi perdagangan dalam era globalisasi, padahal Indonesia sangat tidak siap untuk menyongsong era itu dan ideologi negaranyapun tak memberi peluang untuk itu, tapi “Jakarta” melakukan juga langkah politis itu. Akibatnya undang-undang yang dilahirkan tak memperlihatkan hubungannya dengan kepentingan masyarakat yang hendak diatur dengan undang-undang itu. Pusat terlalu mendominasi kebijakan legislasi nasional, terlebih-lebih pada masa pemerintahan Orde Baru yang memberi peluang yang besar kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan legislasi. Pada masa itu hampir tak ada keinginan daerah yang dapat disahuti dengan baik oleh Pemerintah Pusat bahkan saat sekarangpun setelah keluar Undang-undang Otonomi Daerah, 274 Hikmahanto, Orasi Ilmiah Hukum Sebagai Instrumen Politik : Intervensi atas Kedaulatan Dalam Proses Legislasi di Indonesia, Disampaikan pada Dies Natalis Fakultas Hukum USU,.0p.Cit. 12 Januari 2004. 361 Peraturan Daerah yang secara substantif tak dapat menyimpang dari keinginan Pemerintah Pusat.275 Selama kurun waktu pembentukan undang-undang hak cipta nasional yakni sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 2002 kekuasaan pembentukan undang-undang masih berada di tangan presiden. Artinya undang-undang hak cipta nasional belum ada yang lahir dari atas kewenangan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini tentu membawa sebuah konsekuensi bahwa undang-undang hak cipta nasional yang berlaku hari ini atau yang pernah berlaku pada masa sebelumnya adalah undang-undang yang berasal dari inisiatif pemerintah di bawah kekuasaan pembentuk undang-undang yakni presiden, sekalipun Dewan Perwakilan Rakyat diberikan kewenangan untuk menyetujui. Jika dikemudian hari undang-undang ini terkesan tidak aspiratif, tidak menyahuti aspirasi rakyat dan bahkan menjadi “macan kertas” maka dapat dimaklumi hal itu terjadi lebih dari suatu keadaan dimana rakyat tidak turut memberikan sumbangsih pemikirannya dalam pembuatan undang-undang itu. Apalagi pada waktu itu kewajiban untuk menyampaikan naskah akademik dalam pengajuan rancangan undang-undang belum ditetapkan. Struktur organisasi lembaga pembuat undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama dengan presiden) negara yang rapuh seringkali menjadi penyebab mengapa suatu undang-undang tidak dapat menampung aspirasi rakyat yang berujung pada tidak dapat ditegakkan ketika undang-undang itu diterapkan. 276 Kerapuhan struktur lembaga pembuat undang-undang ini telah dirasakan sejak masa awal berdirinya negara hingga hari ini. Sayangnya putra-putri bangsa ini enggan mempelajari sejarah, tapi selalu terkagum-kagum dengan kebesaran Sriwijaya, Majapahit atau Singosari. Akan tetapi tidak pernah ada yang belajar dari keruntuhan ketiga kerajaan tersebut. Pengalaman kepemimpinan ketiga kerajaan tersebut yang kala itu memerintah secara monarkhi absolut yang bermakna pula bahwa tiap titah raja adalah hukum dalam wilayah negara nusantara ketika itu. 277 275 Wawancara dengan Abdul Hakim Siagian, Mantan Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi, Wakil ketua Komisi Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Provinsi yang juga mengetuai berbagai Ketua Pansus, wawancara tanggal 10 Juli 2013, jam 11.15.00 di Medan. 276 Lebih lanjut lihat Hikmahanto Juwana, Penegakan Hukum Dalam Kajian Law and Development : Problem dan Fundamen Bagi Solusi di Indoensia, Pidato Ilmiah, Disampaikan pada Acara Dies Natalis Ke-56 Universitas Indonesia, Kampus UI Depok tanggal 4 Pebruari 2006, hal 14. 277 Lebih lanjut lihat Paul Michel Munoz, Kerajaan-kerajaan Awal Kepulauan Indonesia dan Semenanjung Malaysia Perkembangan Sejarah dan Budaya 362 Pengalaman sejarah itu akhirnya diwarisi juga oleh Indonesia sebagai suatu negara modern pasca kemerdekaan. Kemerdekaan memang berhasil mengusir penjajah tapi tidak berhasil membangun struktur organisasi negara yang kuat termasuk struktur lembaga pembuat undang-undang. Sebelum diamandemen, Undang-undang Dasar 1945 Pasal 5 dan Pasal 20 meletakkan kekuasaan pembuat undang-undang itu ditangan presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat hanya menyetujui saja. Menurut ajaran Trias Politika,278 kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif haruslah dipisah, agar kewenangankewenangan yang dimiliki oleh lembaga itu lebih bersifat otonom dengan garis-garis batas kewenangan yang jelas. Konsep negara hukumpun menghendaki pemisahan yang jelas antara masing-masing lembaga itu. Akan tetapi di luar tradisi negara hukum dan menyimpang dengan apa yang dipikirkan oleh Rosseau sungguh sangat mengejutkan, Indonesia justru dalam undang-undangnya memberikan kewenangan pembentuk undang-undang kepada eksekutif (presiden) padahal seharusnya kewenangan itu berada di tangan legislatif yakni DPR. Kondisi ini telah berlangsung selama bertahun-tahun. Empat kali perubahan undang-undang hak cipta nasional, masih mengacu pada ketentuan tersebut yakni Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-undang Dasar 1945. 279 Asia Tenggara (Jaman Pra Sejarah – Abad XVI), (Terjemahan Tim Media Abadi), Penerbit Mitra Abadi, Yogyakarta, 2009. 278 Lihat M. Solly Lubis, Ilmu Negara, Mandar Maju, Bandung, 2007. 279 Lembaga pembuat undang-undang adalah sebuah organ atau sub sistem dalam sistem kenegaraan yang berada bersama-sama dengan lembaga eksekutif dan yudikatif. Tidak mungkin dapat dicapai sebuah tujuan untuk mewujudkan cita-cita negara jika organ-organ yang ada di dalam negara itu tidak saling bekerja sama secara kompak atau justru satu lembaga saja yang bekerja tapi lembaga yang lainnya tanpa memiliki kewenangan dan diposisikan sebagai atribut atau alat untuk menjustifikasi seolah-olah produk undang-undang itu telah dilakukan benar-benar menurut konsep negara hukum. Keruntuhan negara lebih banyak diawali karena ketidak kompakan berbagai-bagai komponen dalam suatu negara yang berpangkal pada terpusatnya kekuasaan ditangan satu orang. Sejarah pengelolaan negara di Republik ini mulai zaman pemerintahan Soekarno yang dilanjutkan dengan pemerintahan Soeharto memperlihatkan terpusatnya kekuasaan negara (termasuk kewenangan membuat undang-undang di tangan satu orang) yakni presiden. Akibatnya undang-undang yang diproduk lebih banyak menyahuti keinginan lembaga eksekutif itu dan meninggalkan aspirasi rakyat. Terkadang hukum rakyat yang hidup dan dipatuhi serta dijalankan di berbagai-bagai masyarakat tradisional di Indonesia tidak pernah dijadikan bahan rujukan dalam penyusunan undang-undang termasuk undang-undang hak cipta. Itulah sebabnya ketika gerakan tari (koreografi) dilindungi dalam undang-undang hak cipta asing yang kemudian ditransplantasikan kedalam undang-undang hak cipta nasional tetapi pembuat undang-undang tidak pernah 363 Undang-undang hak cipta nasional yang ada hari ini adalah undang-undang yang sarat dengan pesanan-pesanan negara maju dengan muatan ideologi kapitalis-liberal. Ini dibuktikan dengan beberapa kali perubahan Undang-undang hak cipta itu ditandai dengan intervensi Amerika, dan dua Undang-undang hak cipta terakhir, memuat bahagian penting yang didasarkan pada TRIPs Agreement yang juga dimotorioleh negara-negara kapitalis. Transplantasi hukum asing kedalam undang-undang hak cipta nasional justru menghilangkan banyak nilai-nilai sosial kultural yang selama ini diyakini sebagai nilainilai luhur Bangsa Indonesia. Hilangnya nilai-nilai sosio kultural itu justru membunuh kreativitas bangsa sendiri yang dalam alasan pembuatan undang-undang hak cipta nasional semula dimaksudkan untuk menumbuhkan kreativitas masyarakat Indonesia. Kewenangan yang dimiliki lembaga pembuat undang-undang seumpama sebilah pisau yang tajam akan tetapi kemudian digunakan untuk memotong jari sendiri. Lembaga pembuat undang-undang telah terkoptasi dalam arus pikiran globalisasi dengan muatan ideologi kapitalis-liberal. 280 Ketidak-puasan masyarakat ini jika tidak disikapi akan berdampak pada maraknya pelanggaran hukum yang jika terus dibiarkan akan berkembang menjadi gerakan-gerakan sparatis. 281 Di memasukkan gerakan pencak silat sebagai karya cipta yang harus dilindungi. Itu adalah satu contoh kasus saja bagaimana peristiwa-peristiwa yang berlangsung dalam masyarakat tradisional tidak menjadi menarik bagi kalangan lembaga pembuat undangundang untuk diadopsi kedalam undang-undang hak cipta nasional. 280 Terlalu luas wilayah negeri ini untuk dikorbankan dengan dalih kepentingan nasional yang hanya bercermin dan tercermin dari Jakarta. Terlalu banyak penduduk negeri ini yang akan menderita dan menjadi koban, hanya untuk dan atas nama bangsa dan rakyat Indonesia yang hanya bercermin dan tercermin di “Senayan” . Bahkan mereka yang duduk di “Senayan” pun adalah mereka-mereka yang punya kampung di daerah tetapi sudah menjadi warga DKI. Kebanyakan mereka sukses mendulang kekuasaan untuk dan atas nama “anak kampung mereka” padahal sekalipun ia tak pernah meminum air sumur di kapung itu. Bagimana mungkin mereka dapat menyahuti aspirasi “kampung” nya, bagaimana pula ia dapat memahami roh dan jiwa act locally yang tumbuh di kampung itu. Inilah yang dirasakan oleh daerah dalam konteks intervensi asing ke dalam lembaga legis lasi nasional. Lembaga pembuat undang-undang yang tersentralisir, tidak pernah bisa memberikan kepuasan kepada semua lapisan masyarakat atas undang-undang yang mereka produk apalagi hendak diberlakukan secara unifikasi. Sulit untuk membuat undang-undang yang berlaku secara unifikasi untuk masyarakat yang plural, agaknya faktor inilah yang dominan hingga sampai hari ini upaya untuk menciptakan KUHPidana Nasional dan Hukum Agraria Nasional tak kunjung selesai hingga hari ini. 281 Dahulu zaman Orde Baru, Soeharto memilih wakil presidennya di luar Jawa, kemudian diikuti denga kebijakan mengangkat menteri mewakili Daerah. Aceh dengan pergolakannya selalu mendapat jatah menteri. Belakanganpun SBY mengangkat 364 lain pihak bagi kaum intelektual keadaan semacam ini dapat tumbuh dan disikapi menjadi gerakan moral yang berujung pada gelombang aksi dan jika tidak ditangani secara benar dapat berubah menjadi prahara yang membawa bencana nasional. Desentralisasi dengan sistem otonomi daerah yang sekarang ini agaknya sudah waktunya untuk ditinjau ulang. Secara struktural perjalanannya selama beberapa tahun telah memberikan rekam jejak yang lebih banyak terkesan negatif, seperti berpindahnya aktivitas korupsi dari Pusat ke daerah. 282 Amerika, sekalipun dengan kapitalis liberalnya sulit untuk diterima dalam perspektif Indonesia, tapi hari ini pertumbuhan dan perjalanan bangsa dan negara ini sedang bergerak ke arah sana. Amerika-lah yang memotori gerakan liberal kapitalis itu yang bermakna juga Amerika-lah yang memaksakan instrumen TRIPs Agreement dan itu berarti juga hukum Amerika-lah yang ditransplantasikan ke dalam UU HKI Nasional. Sekalipun hal itu tidak disukai tapi bagi Amerika sesuai dengan struktur dan kultur serta bentuk negara dan sistem pemerintahannya itu yang terbaik hari ini. Ada yang patut ditiru dari negara “federal” itu yakni : kultur hukum Amerika yang diikuti dengan rezim politiknya yang stabil. Kultur politinya berakar pada hak-hak masyarakat sipil, sistem hukum telah terdefinisi dengan baik, peradilan independen, tingkat korupsi rendah, struktur birokrasinya sederhana dan efisien, tidak nepotisme, penyelenggara negara lebih bersifat professional, kreativitas masyaraktnya tumbuh dengan baik. 283 Keadaan demikian dalam banyak hal karena didukung oleh sistem federal yang dianut oleh negaranya dan konsep pemisahan kekuasaan – legislatif, eksekutif dan judikatif – dipegang teguh. Dalam tataran penegakan hukum intervensi eksekutif menjadi sangat kecil, karena kewenangan eksekutif telah dibatasi dengan baik. Demikian menterinya dari kalangan Aceh, kini setelah Aceh jadi daerah intimewa, gejolak mulai reda tak ada lagi orang Aceh masuk dalam kabinet menteri. 282 Sumber-sumber penghidupanpun terpusat di Jakarta. Sehingga ibu kota diserbu pencari kerja. Uangpun lebih banyak berputar di Jakarta daripada di daerah. Jakarta menjadi kota terpadat di dunia. Pada menjelang lebaran energi penyelenggara negara tersita untuk urusan mudik, yang tak pernah ada di belahan dunia manapun. Harus ada keberanian untuk meninggalkan tradisi buruk, yakni “mensakralkan” kelanggengan. Padahal tak ada yang harus ditakuti, jika itu dapat mengantarkan bangsa ini kepada negeri yang aman, damai, sentosa, sejahtera, adil dan makmur di ridhoi oleh Tuhan Yang maha Esa. Pengalaman bangsa ini mentransplantasi norma hukum asing tanpa mentransplantasi struktur dan kulturnya telah memperlihatkan kegagalannya. 283 Lebih lanjut lihat Martin Wolf, Globalisasi Jalan Menuju Kesejahteraan, (Terjemahan : Samsudin Berlian), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 81. 365 juga campur tangan eksekutif ke dalam kerja-kerja legislatif (parlemen) hampir tak mungkin dapat dilakukan, karena telah dibatasi oleh koridor masing-masing. Demikian juga kalau dirujuk sistem federasi yang dianut oleh Malaysia. Lembagai Pemerintah (executive), Lembaga Perundang-undangan (legislative) dan Lembaga Kehakiman (judiciciary) memegang fungsi dan peranan yang terpisah. Sekalipun ketiganya berada di bawah Yang di-Pertuan Agong, akan tetapi lembaga yang disebut terakhir ini hanya “simbol” Pemimpin Negara Malaysia. Pilihan terhadap sistem federal ini didasarkan pada kenyataan sejarah dan fakta empirik bahwa Malaysia – sama dengan Indonesia – adalah negara yang plural, baik dari segi keberagaman agama maupun etnik. Itulah sebabnya Pemerintah Kolonial Inggeris untuk memperkukuh keadaan “multi ethnic” itu perlu diterapkan sisitem federalisme dengan mencontoh pola yang ada di Kanada. Malaysia demikian ungkap Syed Azman merupakan gabungan dari 13 negara bagian dan fungsi dan peranan, hak dan kewajiban, serta masibng-masing kewenangan antara pemerintah pusat (Federal Goverment) dengan pemerintah negara bagian diatur dalam Perundang-undangan Perserikatan (Undang-Undang dasar Negara) dengan sistem pembagian kekuasaan yang jelas. 284 Kondisi ini telah menghilangkan “beban pikiran” pemerintah terhadap kemungkinan perjuangan separatis untuk mendirikan negara baru yang terpisah dari Malaysia seperti yang dihadapi Indonesia selama kurun waktu kemerdekaan hingga hari ini. Perjuangan Rakyat Aceh, Papua dan Maluku Selatan sampai hari ini masih menjadi beban politik yang tidak sedikit menguras energi. Sehingga konsentrasi pembangunan pada sektor lain menjadi terganggu, tidak seperti Malaysia pembangunan dan pemerataan tampak nyata terutama pada masa kepemimpinan Mahathir dan dan dengan gagah berani terangterangan menentang kebijakan Amerika. 285 Perbandingan dengan sistem federal dengan negara kesatuan lebih pada persoalan kecerdasan intelektual untuk memahami bahwa dalam bangsa yang multi etnis tak mungkin kesatuan (unity) dapat dilakukan, tapi yang mungkin bisa dilakukan adalah persatuan dalam keragaman (uniformity). Pandangan seperti itu perlu digulirkan dalam tulisan ini, karena secara struktural hukum sangat berpengaruh pada pilihan bentuk negara ini. Negara sebagai sebuah sistem yang 284 Lebih lanjut lihat Syed Azman dalam Adnan Buyung Nasution et.all, Federalisme Untuk Indonesia, Kompas, Jakarta, 1999, hal. 92. 285 Ramon V. Navaratnam, Malaysia’s Economic Recovery Policy Reforms for Economic Sustainability, Pelanduk Publications, Malaysia, 2001. 366 menempatkan hukum sebagai sub sistem di dalamnya akan sulit untuk dapat mengakomodir hak-hak masyarakat lokal di daerah, sulit untuk mengakomodir nilai-nilai hukumn lokal (act locally) apalgi jika dihadapkan dengan politik hukum negara yang harus mengakomodir tuntutan negara asing dengan sistem hukum asing-nya. Seumpama kesebelasan PSMS (Persatuan Sepak Bola Medan Sekitarnya) diajak untuk bertarung di Liga Eropa, konon pula dalam perebutan Piala Dunia, dan ini dalam pepatah Melayu disebut dengan “menggantang asap”. Supaya pekerjaan menggantang asap ini tidak terus menerus terjadi dalam bangsa yang besar ini, maka perlulah wacana federasi ini digulirkan. Jika wacana ini dapat diterima publik dan dikukuhkan dalam undang-undang, bentuk negara federal ini diharapkan dapat menciptakan iklim birokrasi yang lebih efisien dan efektif. Penegakan hukum dan keadilan dapat lebih menyentuh semua lapisan masyarakat,terutama mengenai keadilan dalam bidang ekonomi dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah ( economic equality and regional equality ) sampai pada penghematan ongkos-ongkos politik yang setiap 3,5 hari sekali melakukan Pilkada untuk daerah Pemerintah Kota/Kabupaten dan Propinsi. Demikian juga pemanfaatan sumberdaya baik itu alam maupun manusia dapat dioptimalkan untuk kepentingan daerah, tidak seperti sekarang secara kasat mata diangkut dan terpusat di “Jakarta”. Sehingga dengan demikian cita-cita masyarakat adil dan makmur seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dapat terwujud, dan legislatif (parlemen daerah) dapat lebih terkonsentrasi merumuskan arah dan politik hukum lokal ke depan dengan “istiqamah” menjadikan the original paradigmatic value of Indonesian culture and society sebagai landasan pembentukan hukum di daerah, sedangkan pada tataran Pemerintah Pusat, Legislatif Pusat (Parlemen Pusat) merumuskan perangkat-perangkat hukum yang lebih mengutamakan hal-hal yang berhubungan dengan organisasi Internasional dalam pergaulan di dunia yang serba terbuka. Sehingga politik hukum di belah menjadi dua arah, satu untuk internal di arahkan kepada pemerintah lokal (negara bagian) untuk urusan hukum eksternal di rumuskan oleh pemerintah Pusat diputus melalui Parlemen Pusat. Dengan demikian kewenangan legislatif seperti yang terjadi selama ini tidak seperti kata pepatah,pisau tajam pemotong jari. Kekuasaan legislatif yang begitu besar digunakan untuk membunuh kreativitas anak bangsa sendiri. Pilihan-pilihan politik pragmatis dalam pembentukan hukum dapat segera diakhiri. 367 2. Lembaga Penegak Hukum (Yudikatif) Lembaga penegak hukum adalah salah satu instrument dalam proses law enforcement yang sesungguhnya merupakan kewenangan yudikatif. Karena itu semua tindakan lembaga penegak hukum selalu dimaknai sebagai “projustisia”. Sulit untuk dimengerti dalam sejarah perjalanan bangsa ini salah satu lembaga penegak hukum terdepan yaitu kepolisian pernah ditempatkan bersama-sama dengan Angkatan Bersenjata (ABRI, AURI dan ALRI) ke dalam institusi Pertahanan Negara. Dikemudian hari, Kepolisian ditempatkan sebagai institusi tersendiri padahal di banyak negara kepolisian ditempatkan dalam lembaga atau departemen dalam negeri. Sejarah perjalanan dan keberadaan institusi Kepolisian yang telah mengalami posisi dan kedudukan yang berganti-ganti dalam kelembagaan negara sedikit banyaknya telah mempengaruhi perilaku personil dan perilaku kelembagaan dalam praktek penegakan hukum di negeri ini. Posisi kepolisian yang ditempatkan sebagai penyidik dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 telah menjadikan institusi ini sebagai garda penegakan hukum terdepan. Ketika dalam perjalanannya entah itu disebabkan karena melemahnya fungsi pengawasan hukum terhadap lembaga ini atau karena lembaga ini merasa tidak perlu lagi diawasi oleh hukum dikemudian hari kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini semakin memudar. Sebagai penyidik, kepolisian telah menyiapkan “bahan-bahan yang sudah siap untuk dimasak” dan diserahkan kepada kejaksaan selaku penuntut umum. Pihak kejaksaanpun segera menggelar persidangan bersama-sama dengan hakim dan polisi dihadirkan juga dalam persidangan untuk memberikan keterangan-keterangan tentang apa yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Akan tetapi dalam banyak kasus, ketiga institusi ini justru “menjalin kerjasama” yang berujung pada apa yang disebut dengan mavia peradilan. Puncaknya hilang kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan diikuti dengan pembentukan lembaga ekstraordinary (ad hoc) yang dikenal dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam perjalanan selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi ternyata lebih mampu menyahuti cita-cita penegakan hukum. Keadaan ini justru tidak membawa lebih baik secara kelembagaan, karena situasi ini kemudian memicu konflik antara sesama aparat penegak hukum yang telah ada sebelumnya. Konflik internal antara sesama institusi penegak hukumpun sering muncul. Sebut saja misalnya konflik antara lembaga KPK dengan Polri, lembaga Kejaksaan dengan Mahkamah Agung dan itu tidak termasuk konflikkonflik yang dipicu dari persoalan-persoalan yang bersifat individu lalu 368 kemudian dibawa ke ranah lembaga. Yang masih terngiang dalam ingatan adalah konflik antara KPK dengan Polri yang harus diakhiri dengan “turun tangan” presiden untuk memberikan solusi walaupun solusi itu pada akhirnya adalah tidak menjernihkan perseteruan antara kedua lembaga itu. Masih ada tersembunyi “sejumlah dendam” yang sewaktu-waktu akan dapat muncul kembali. Terminologi “cicak dan buaya” adalah terminologi yang menggambarkan betapa situasi strutur organisasi kelembagaan dalam pemerintahan yang disebut negara masih penuh dengan intrik, kecurigaan yang pada akhirnya sulit untuk menjalin suatu kerjasama yang harmonis. Kondisi penegakan hukum hari ini telah pula terbagi-bagi secara hirarkis. KPK hanya menangani perkara-perkara korupsi yang besar, sementara perkara-perkara yang kecil masih ditangani oleh aparat kepolisian. Tradisi penegakan hukum menjadi tidak lagi bernuansa penciptaan situasi keamanan dan kenyamanan serta memberikan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat. Pengklasifikasian perkara “besar” dengan perkara-perkara yang “kecil” menimbulkan kecemburuan antara sesama aparat penegak hukum. Besar kecilnya perkara itu diukur pula dari nilai ekonomis yang melekat dalam kasus itu sehingga perkara-perkara yang secara kasat mata dianggap tidak memiliki nilai ekonomis yang tinggi menjadi terabaikan. Begitulah yang terjadi dalam lapangan perlindungan karya sinematografi. Pembajakan atau pelanggaran terhadap karya sinematografi melalui produksi illegal berupa kepingan VCD dan DVD tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum yang masuk dalam kategori kejahatan berskala besar. Tidak ada juga yang dapat menjelaskan bagaimana kerusakan moral hukum yang ditimbulkan dari proses pembiaran terhadap aktivitas pembajakan atau pelanggaran hak cipta itu. Belum lagi terhadap kasus penyewaan yang secara tegas dilarang dalam undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002. Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 19 Tahun 2002 menyatakan : Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas Karya Sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan di atas. Jika redaksi pasal tersebut dirumuskan dalam bahasa yang sederhana terdapat 2 (dua) jenis karya cipta yang jika disewakan harus mendapat persetujuan atau izin dari pencipta atau pemegang haknya yaitu : 369 1. 2. Karya sinematografi Program komputer Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, maka seseorang dilarang untuk menyewakan karya cipta sinematografi (termasuk juga program komputer) untuk tiap-tiap kepentingan yang bersifat komersial jika tidak diberikan persetujuan atau izin oleh pencipta atau pemegang hak cipta tersebut. Hak untuk memberikan izin atau hak untuk melarang oleh undang-undang ini diberikan kepada pencipta atau pemegang haknya. Pelanggaran atas ketentuan itu termasuk dalam kategori pidana dengan sifat delik sebagai delik biasa. Akan tetapi tidak ada reaksi apapun dari aparat Kepolisian terhadap peristiwa pidana itu. Di samping itu ketentuan pasal ini pun masih menyimpan konflik normatif jika dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum perdata. Hak cipta dipahami sebagai hak kebendaan yang immateril yang tunduk pada azas-azas (prinsip) hukum benda. Seseorang yang telah mendapatkan hak menurut ketentuan KUHPerdata yakni melalui : 1. Perlekatan 2. Daluwarsa 3. Pewarisan 4. Wasiat 5. Hibah atau jual beli. 286 diposisikan sebagai pemegang hak absolut. Dalam konteks kepemilikan atas benda yang telah dimiliki atau yang telah diperoleh berdasarkan ketentuan Pasal 584 KUH Perdata tersebut, maka si pemilik boleh berbuat bebas atas benda yang ia miliki tersebut. Si pemilik bebas untuk menikmati kegunaan atas benda tersebut dengan leluasa dengan kedaulatan sepenuhnya asal penggunaan itu tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan umum yang ditetapkan oleh kekuasaan yang berhak untuk menetapkannya, tidak mengganggu hak orang lain dan seterusnya. 287 Hak apa sesungguhnya yang dialihkan oleh pencipta atau oleh si pemegang hak atas karya sinematografi ? Jawabnya adalah hak untuk menikmati rangkaian cerita film atas karya sinematografi tersebut. Hak untuk menikmati benda immateril yang melekat pada karya sinematografi tersebut yang dimuat dalam kepingan VCD, DVD atau dalam bentuk disk blue ray. Tentu saja hak untuk menikmati itu setelah seseorang memperoleh hak kebendaan immateril itu dengan cara yang 286 Lebih lanjut lihat ketentuan Pasal 584 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 287 Lebih lanjut lihat Pasal 570 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 370 dibenarkan oleh undang-undang (vide Pasal 584 KUHPerdata) si pemilik hak memiliki kewenangan yang bebas untuk menggunakan termasuk membuat perikatan dengan pihak ketiga lainnya seperti menjualnya, menyewakannya, menghibahkannya, mewasiatkannya dan mewariskannya. Akan tetapi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 19 Tahun 2002 justru memberikan batasan, apabila karya sinematografi itu disewakan haruslah mendapat izin atau persetujuan dari pencipta atau pemegang hak. Jika demikian halnya mengapa dia harus menciptakan karya itu ? Jawabannya adalah agar dia dapat memperoleh kompensasi dari hasil karya ciptanya. Akan tetapi jika setelah mendapatkan kompenasi seseorang yang mendapatkan hak darinya kemudian dibatasi haknya seperti untuk menyewakan kepada pihak ketiga, sudah barang tentu hal ini bertentangan dengan asas yang terkandung dalam Pasal 570 KUH Perdata. Dalam sebuah wawancara yang kami lakukan dengan pihak pemilik cinema club – bioskop keluarga diperoleh keterangan sebagai berikut : Pimpinan Cinema Club - Bioskop Keluarga menuturkan : Kepingan DVD dan VCD serta Disc Blue Ray (DBR) kami beli dari distributor di Jakarta, khusus untuk DBR. Untuk kepingan DVD dan VCD kami membeli dari toko-toko resmi di Kota Medan. Harga untuk kepingan DBR berkisar Rp. 450.000,- – Rp. 500.000,- sedangkan untuk VCD dan DVD harga berkisar Rp. 50.000,- - Rp. 60.000,- dan mendapat potongan harga 10% s/d 15%. Kepingan DVD, VCD maupun DBR kami beli dengan jual beli putus, artinya setelah kami beli tidak ada ikatan apapun dengan pihak distributor. Harga ini memang termasuk mahal jika dibandingkan dengan kepingan VCD dan DVD yang non original. Akan tetapi kami memang harus membeli yang original sebab kami harus menampilkan gambar yang terang serta bersih dan tidak macet (sangkut saat diputar). 288 Merujuk pada penuturan pimpinan Cinema Club – Bioskop Keluarga tersebut di atas, dapat dipahami bahwa kepingan VCD, DVD dan DBR dibeli dengan jual beli putus tanpa ikatan atau klausul tambahan setelah jual beli itu dilakukan. Jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 570 KUHPerdata, maka pimpinan Cinema Club – Bioskop Keluarga berhak untuk mengalihkan kenikmatan atas hak yang melekat pada kepingan VCD, DVD dan DBR tersebut kepada orang lain dalam bentuk menyewakan tanpa mendapat persetujuan atau izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Seyogyanyalah pihak pencipta atau pemegang hak cipta tidak boleh melarang pimpinan Cinema Club Bioskop Keluarga tersebut untuk menyewakan kepingan VCD, DVD dan DBR tersebut kepada orang lain, karena memang itulah 288 Wawancara dengan William Hatapary, Pimpinan Cinema Club – Bioskop Keluarga, Medan, tanggal 19 Juni 2013. 371 kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Apakah tindakan pihak Cinema Club – Bioskop Keluarga termasuk pada perbuatan melawan hukum atau perbuatan kriminal ? Semestinya perbuatan itu tidak termasuk pada perbuatan melawan hukum, hanya saja ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 19 Tahunm 2002 tersebutlah yang menjadi klausul undang-undang yang mengkriminalisasi tindakan pimpinan Cinema Club – Bioskop Keluarga tersebut. Pimpinan Cinema Club – Bioskop Keluarga dalam aktivitasnya tidak hanya menyediakan film-film (baca : karya sinematografi) yang mereka sediakan sendiri. Para konsumen ada yang membawa kepingan DVD, VCD dan DBR yang mereka beli sendiri untuk kemudian ditonton bersama kelurga dan para koleganya di Studio Cinema Club – Bioskop Keluarga tersebut. Tentu saja untuk tindakan yang terakhir ini tidak dapat “dijerat” dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 19 Tahun 2002. Ketentuan ini diambil alih dari TRIPs Agreement, tapi Undang-undang Hak Cipta Indonesia memberi syarat maksimum dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 yaitu : Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak” termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada public melalui sarana apapun. Ketidak adilan tergambar dalam kasus ini. Seseorang yang membawa kepingan DVD, VCD dan DBR dari rumahnya sendiri, lalu kemudian ditonton di studio Cinema Club-Bioskop Keluarga, tindakan seperti ini tidak dianggap sebagai perbuatan kriminal atau perbuatan melawan hukum karena kepingan DVD, VCD dan DBR itu dibeli sendiri oleh pihak yang akan menonton. Sebaliknya jika kepingan DVD, VCD dan DBR itu disewa (tidak dibeli) justru perbuatan itu menjadi perbuatan kriminal atau perbuatan melawan hukum. Aktivitas semacam itu memang tidak dipahami oleh pihak pimpinan Cinema Club – Bioskop Keluarga. William Hatapary menuturkan : Film-film yang kami sewakan disini adalah film-film yang termasuk dalam kategori box office. Semuanya film-film Amerika. Dulu kami pernah mencoba untuk menyediakan film-film Asia, akan tetapi peminatnya tidak ada. Film-film ini semuanya film-film yang sedang menduduki peringkat atas penonton di dunia. Tapi kami baru mendapatkan kepingan DVD, VCD dan DBR setelah film-film itu diputar 1 sampai dengan 2 bulan di bioskopbioskop dunia karena pihak distributor tidak mengedarkan film-film itu dalam 372 kepingan DVD, VCD dan DBR sebelum masa putar di bioskop berakhir. Harga untuk tiap-tiap kali satu masa putar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per satu ruangan. Ada juga diantara tamu-tamu yang datang membawa kepingan DVD, VCD dan DBR sendiri dan itu mereka bawa dari rumah. Bagi kami itu tidak menjadi masalah, akan tetapi kami mengurangi uang sewanya menjadi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per satu kali masa putar untuk satu ruangan. 289 Dari penuturan pimpinan Cinema Club – Bioskop Keluarga tersebut terungkap bahwa sebenarnya hanya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) uang penyewaan yang riil dari tiap-tiap kepingan DVD, VCD dan DBR tersebut. Untuk mengembalikan modal sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pihak Cinema Club – Bioskop Keluarga paling tidak harus mendapatkan pelanggan untuk 18 kali masa putar untuk satu ruangan. Jadi sebenarnya sangat minim yang diperoleh oleh pihak Cinema Club-Bioskop Keluarga jika diharapkan semata-mata dari hasil penyewaan DVD, VCD dan DBR tersebut. Secara ekonomis, untuk menutupi seluruh biaya operasional Cinema Club-Bioskop Keluarga ini tidak sepenuhnya tergantung pada penyewaan DVD, VCD dan DBR saja akan tetapi berharap pada penyewaan ruangan dan penjualan makanan serta minuman. Gagasan semula untuk menghitung penghasilan dari pembukaan Cinema Club – Bioskop Keluarga ini tidak digantungkan pada penyewaan DVD, VCD dan DBR ini akan tetapi adalah gagasan dan ide yang timbul pada saat akan mendirikan usaha pencucian mobil sebagaimana diungkapkan William Hatapary sebagai berikut : Semula saya akan mendirikan usaha doorsmeer atau usaha pencucian kendaraan. Seringkali pelanggan yang akan melakukan pencucian kendaraan terlalu lama menunggu dan menimbulkan kebosanan. Untuk mengantisipasi kebosanan itu kami sediakan satu ruangan untuk menonton film-film cerita yang diputar melalui diskplayer. Sambil menunggu kendaraan selesai dicuci, para pelanggan terus menonton. Sayangnya, setelah kendaraan selesai dicuci film yang mereka tonton belum berakhir, akhirnya para pelanggan kembali menunggu film cerita habis diputar. Lalu saya berfikir bagaimana kalau dibuat usaha yang menyediakan hiburan dalam bentuk menyewakan ruangan untuk pemutaran film-film bioskop. Inilah awal gagasan saya mendirikan usaha Cinema Club – Bioskop Keluarga ini. 290 Ungkapan pimpinan Cinema Club – Bioskop Keluarga di atas menggambarkan bahwa aktivitas penyewaan DVD, VCD dan DBR bukanlah aktivitas yang utama. Penyewaan DVD, VCD dan DBR tersebut adalah sebagai instrument saja untuk dapat menyewakan 289 William Hatapary, Ibid. 290 William Hatapary, Ibid. 373 ruangan agar para keluarga dapat rileks sambil makan minum. Intinya adalah terlalu jauh dari rasa keadilan jika pihak pengelola Cinema Club – Bioskop Keluarga harus meminta persetujuan atau meminta izin dari pencipta atau pemegang hak untuk aktivitas tersebut. Apalagi sejak awal pihak Cinema Club – Bioskop Keluarga sendiri tidak pernah menonton film-film yang telah mereka beli dalam bentuk kepingan DVD, VCD dan DBR tersebut. Jadi hak kekayaan intelektual berupa hak untuk menikmati karya sinematografi yang melekat pada kepingan sama sekali tidak untuk dinikmatinya sendiri, akan tetapi diberikan kenikmatannya kepada pihak ketiga dengan membayar sewa. 291 Meskipun pembuat undang-undang lalai dalam membuat sanksi atas pelanggaran ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tersebut akan tetapi konsekuensi hukumnya tetap ada. Jika pencipta dan pemegang hak berkeberatan, tuntutan pidana dapat saja dilakukan dengan dalil tidak mengindahkan peraturan undangundang, tidak menghormati hak pencipta yang menimbulkan rasa tidak menyenangkan atau dapat dilakukan melalui gugatan ganti rugi karena telah merugikan pihak pencipta dan pemegang hak cipta. Penegakan hukum tidak sama dengan penegakan undangundang. Undang-undang adalah sebahagian dari hukum. Dalam proses penegakan hukum, haruslah dipahami bahwa yang ditegakkan itu adalah sistem hukum yang berisikan substansi, struktur dan kultur sebagaimana yang diungkapkan oleh Friedman. 292 Pandangan Friedman yang menempatkan hukum dalam satu sistem bermakna bahwa masing-masing komponen yang terdiri dari substansi struktur dan kultur akan saling terhubung dan saling 291 Jika seseorang memiliki benda materil yang ia beli sebelumnya da ri pihak pemilik benda itu misalnya saja berupa tanah, rumah atau mobil. Apakah si pemilik yang mendapatkan hak dengan cara membeli itu harus meminta izin atau mendapat persetujuan dari pihak pemilik pertama agar ia dapat menyewakan tanah, rumah, mobil tersebut kepada pihak ketiga ? Jawabnya : tentu tidak. Karena Pasal 570 KUHPerdata dengan tegas menyatakan bahwa si pemilik dapat berbuat bebas atas obyek hak milik yang telah ia peroleh dengan cara yang benar menurut hukum untuk dapat berbuat bebas terhadap benda itu. Dalam hak cipta yang dilarang itu bukanlah hak untuk menyewakan, yang dilarang adalah hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan. 292 Lebih lanjut lihat Lawrence M. Friedman, The Legal System A Social Science Perspective, Russell Sage Foundation, New York, 1975. Bandingkan juga dengan Padmo Wahjono, Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila, Rajawali, Jakarta, 1983. Lihat lebih lanjut Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991. Bandingkan juga dengan Elly Erawaty, dkk, Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011. Bandingkan juga dengan Lili Rasjidi, dan I.B. Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remadja Rosdakarya, Bandung, 1993. 374 berkaitan. Artinya tidak cukup hanya isi hukumnya saja yang baik, akan tetapi harus diikuti dengan struktur dan kulturnya. Demikian juga tidak cukup strukturnya saja yang baik akan tetapi harus diikuti dengan substansi dan kulturnya. Demikian seterusnya jika substansi dan strukturnya saja yang baik jika tidak diikuti dengan kulturnya maka hukum juga tidak akan dapat mencapai tujuannya. Dalam proses penegakan hukum, tujuan hukum yang hendak dicapai simetris dengan komponen-komponen dalam sistem hukum yaitu untuk menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan.293 Konsekuensinya hukum harus dilihat dalam berbagai dimensi. 294 Dalam praktek penegakan hukum, khususnya dalam bidang karya cipta sinematografi dalam sejarah perlindungan hak cipta di Indonesia sampai hari ini memperlihatkan sisi yang tidak menggembirakan. Praktek pelanggaran hukum bidang karya sinemaografi ini tentu tidak terlepas dari faktor bahwa budaya penegakan hukum hak cipta bukanlah budaya hukum yang tumbuh atau hukum yang hidup yang berakar pada kultur Bangsa Indonesia. Bidang hukum ini adalah termasuk bidang hukum yang ditransplantasikan dari hukum asing. Ditemukan banyak faktor kesulitan dalam penegakan hukum yang sumber kulturalnya tidak berakar pada budaya lokal. Jika seseorang melakukan tindak pidana pencurian atas benda yang nyata atau benda berwujud, budaya hukum masyarakat setempat sejak awal telah meyakini bahwa perbuatan itu adalah salah. Orang yang 293 Lebih lanjut lihat Gustaf Redbruch Gustav Radbruch, Rechts-Philosophie, K.F. Koehler Verlag Stuttgart, Germany, 1956. 294 Seringkali terdengar ungkapan di masyarakat bahwa hukum tidak tegak. Hukum yang diterapkan tidak memberikan rasa keadilan. Hukum malah bagi kalangan pelaku ekonomi dirasakan tidak hanya tidak memberikan manfaat akan tetapi juga menghambat kreativitas mereka. Pertanyaan yang selalu muncul kemudian adalah bagaimana dengan praktek penegakan hukum selama ini? Aktivitas polisi, jaksa, hakim, pengacara terus berjalan. Kantor polisi setiap hari penuh dengan jumlah manusia (apakah semuanya untuk kepentingan projustisia atau tidak, itu persoalan lain). Begitu juga kantor Kejaksaan dan Kantor Pengadilan tak pernah sepi dari kerumuna n manusia, tapi mengapa selentingan bahwa hukum tidak tegak, hukum tidak berjalan masih terus berkumandang. Ternyata hukum tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang saja. Hukum memiliki paradigma ganda (multi paradigm). Hukum tidak dapat ditempatkan dalam satu garis linier. Hukum berada pada garis nonlinier. Itulah yang menyebabkan perspektif sosiologis-empirik menjadi kajian yang paling banyak dilakukan, yakni sebuah kajian untuk melihat pelaksanaan hukum di tengah-tengah masyarakat untuk melihat hukum yang hidup atau dengan meminjam istilah yang digunakan oleh Sulistyowati Irianto untuk melihat hukum yang bergerak di tengah-tengah masyarakat. Lebih lanjut lihat Sulistyowati Irianto, Hukum Yang Bergerak Tinjauan Antropologi Hukum, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009. 375 melakukan transaksi jual beli atas barang yang diketahuinya bersumber dari perbuatan yang salah, secara sadar ia juga mengakui tindakan yang ia lakukan itu adalah juga merupakan tindakan yang salah. Adalah berbeda ketika seorang yang mengeluarkan uang untuk pembelian sebuah VCD atau DVD hasil karya sinematografi, si pembeli tak pernah menyadari bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang salah. Jika kemudian perbuatan seperti itu harus juga dikategorikan sebagai perbuatan yang salah atau menurut terminologi hukum pidana sebagai suatu tindak pidana maka kesulitan pertama yang ditemukan adalah bagaimana membangun persepsi yang sama antara pihak aparat penegak hukum dengan pihak konsumen termasuk juga produsen illegal itu. Di sisi lain pihak aparat penegak hukum khususnya dalam penegakan hukum hak cipta, walaupun undang-undang telah menunjuk penyidik Pegawai Negeri Sipil namun masyarakat tetap memandang bahwa penyidik itu adalah polisi. Polisilah sebenarnya sebagai garda terdepan untuk melakukan penegakan hukum dalam bidang karya sinematografi. Sementara itu, persepsi masyarakat terhadap profesi polisi selaku penegak hukum saat ini sedang merosot. Profesionalisme aparat kepolisian setiap hari mendapat sorotan bernuansa negatif di banyak media sehingga muncul opini bahwa polisi tidak dapat diharapkan untuk melakukan penegakan hukum. Bak kata pepatah : menyapu dengan sapu yang kotor, aparat kepolisian sulit untuk melakukan pembersihan karena di mata masyarakat, di tubuh aparat kepolisian terdapat sejumlah noda. 3. Lembaga Pemerintah (Eksekutif) Kondisi pemerintahan Indonesia hari ini jauh berbeda dengan kondisi pemerintahan pada masa-masa sebelumnya. Jika pada periode pemerintahan Bung Karno, Indonesia disibukkan dengan berbagai konflik internal yakni pergulatan politik dalam negeri dan secara internal masih ada urusan-urusan dengan klaim pemerintah Hindia Belanda terhadap Indonesia khususnya mengenai Irian Barat. Pada masa pemerintahan Soeharto, keadaan politik dalam negeri lebih kelihatan stabil akan tetapi persoalan birokrasi cenderung berpusat di tangan satu orang yakni presiden. Partai-partai politik pun pada masa itu diarahkan untuk mendukung kebijakan pemerintahan orde baru. Nyaris tidak ada oposisi pada masa pemerintahan Soeharto. Akan tetapi kreativitas dan kebebasan rakyat pada masa itu menjadi terhambat. Pasca pemerintahan reformasi terbuka peluang lebar untuk tumbuhnya alam demokrasi yang lebih berkeadilan. Akan tetapi dalam perjalannya 376 melahirkan pemimpin-pemimpin yang penuh dengan kehati-hatian yang berujung pada sikap ragu-ragu. 295 Memang masyarakat menjadi lebih terbuka pada pasca pemerintahan reformasi akan tetapi keterbukaan itu justru menimbulkan musuh-musuh yang baru seperti kata Popper. 296 Diantara musuh-musuh itu adalah masyarakat semakin berani dan terangterangan melakukan aksi-aksi untuk dan atas nama demokrasi dan kebebasan. Akan tetapi bersamaan dengan itu nilai-nilai ke-Indonesiaan memudar, ideologi Pancasila dikesampingkan. Nilai-nilai sosial, kultural dan religi tidak lagi dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan berbagai aktivitas. Puncaknya lembaga pemerintahan yang dipimpin oleh kalangan eksekutif mulai dari Presiden sampai pada pemimpin di tingkat kelurahan memperlihatkan sikap keraguraguannya untuk mengambil berbagai keputusan. Keragu-raguan itu diawali dari adanya isu pelanggaran HAM jika tindakan penegakan hukum dilakukan secara represif. Keraguan berikutnya adalah ketidak pastian dalam penegakan hukum. Perbedaan antara kebijakan dan tindak pidana terlalu tipis dan begitu mudah untuk ditafsirkan, sehingga berbagai kebijakan yang diambil oleh para eksekutif di kemudian hari dalam proses hukum berubah menjadi tindak pidana korupsi. Demikian juga perbedaan antara sekatan-sekatan perdata dan sekatan-sekatan pidana semakin menipis sehingga hubungan-hubungan keperdataan begitu mudah ditafsirkan menjadi peristiwa pidana. 297 Kedua faktor ini sangat dominan dalam mempengaruhi perilaku eksekutif mulai dari pusat sampai ke daerah. 298 295 Lebih lanjut lihat Riwanto Tirtosudarmo, Mencari Indonesia DemografiPolitik Pasca-Soeharto, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007. Lihat juga Tjipta Lesmana, Dari Soekarno Sampai SBY, Gramedia, Jakarta, 2008. 296 Lebih lanjut lihat Karl R. Popper, The Open Society and Its Enemies, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1971. 297 Lebih lanjut lihat Sulistyowati Irianto, Antonius Cahyadi, Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana Studi Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008. 298 Di beberapa kasus di Kota Medan banyak para kontraktor tidak bersedia untuk mengerjakan berbagai proyek karena khawatir akan ancaman hukuman. Bahkan para kepala dinas mengundurkan diri dari jabatannya karena khawatir suatu hari pertanggungjawabannya sebagai pengelola keuangan akan menimbulkan unsur-unsur peristiwa pidana yang mengancam pribadinya. Keraguan pimpinan eksekutif ini terlihat pula selama periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak pernah mengambil putusan yang tegas terhadap persoalan-persoalan kenegaraan. Lihat saja bagaimana perseteruan antara lembaga-lembaga penegak hukum yang tak kunjung selesai sampai hari ini, kalaupun dianggap selesai karena adanya “perdamaian” sesaat, mungkin dikemudian hari perseteruan itu akan terulang kembali. Banyak pihak yang mengatakan presiden ragu-ragu dalam mengambil keputusan seperti kata pepatah Melayu “Orang 377 Dampak yang ditimbulkannya kemudian adalah masyarakat semakin merajalela bahkan dengan terang-terangan melakukan perlawanan terhadap aparat penegak hukum. Sebagai reaksi terhadap tindakan masyarakat tersebut, aparat penegak hukum justru lebih merasa aman dan lebih merasa nyaman jika tidak melakukan reaksi apapun terhadap tindak pidana pelanggaran hak cipta yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Secara sadar telah terjadi proses pembiaran struktural. 299 Aparat Kepolisian misalnya, lebih baik membiarkan saja peristiwa itu berlangsung meskipun ada rasa takut di kalangan pedagang barang-barang illegal itu pada saat aparat kepolisian itu melakukan razia terhadap barang-barang hasil bajakan tersebut. Akan tetapi, setelah razia tersebut selesai dilakukan dan pada saat para aparat kepolisian berlalu masyarakat kembali menggelar jualannya berupa VCD dan DVD hasil pelanggaran karya sinematografi. Kehadiran polisi seperti kata pepatah : Biduk lalu kiambang bertaut, tak ada juga yang dapat menjadi kesan positif bagi para penjual hasil karya sinematografi bajakan. Seberapa besarpun razia dilakukan, pelanggaran hukum terus berlangsung. Tingkat kesadaran hukum masyarakat seolah-olah bak air di daun keladi, tak ada bekas yang dapat menumbuhkan kesadaran hukum baru bahwa tindakan pembajakan dan menjual hasil bajakan terhadap karya sinematografi adalah sebuah kejahatan. Kondisi ini tidak terlepas dari berbagai faktor. Penegakan hukum yang selama ini dilakukan secara selektif, tebang pilih membuat masyarakat semakin hari semakin menipis kepercayaannya terhadap aparat penegak hukum. Bak kata pepatah penegakan hukum yang dilakukan selama ini mengacu pada prinsip tebang pilih seperti : Tepat di mata dipicingkan, tepat di perut dikempiskan. Ketika terjadi “transaksi-transaksi bisnis di lapangan“ seiring dengan itu “transaksi hukumpun” berlangsung juga. Dampak yang ditimbulkannya kemudian adalah pertumbuhan dunia perfilman nasional (tentu saja dunia perfilman internasional) mengalami kemunduran. Jika pada suatu masa industri perfilman nasional pernah berkembang dengan baik akan tetapi pada beberapa tahun belakangan ini dunia perfilman bagai kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Kreativitas pencipta semakin hari semakin memperlihatkan gamang mati terjatuh”. Ketika berada di puncak ketinggian justru tidak mengambil langkah-langkah pasti untuk orang-orang yang berada di bawah, akan tetapi justru melihat ketinggian itu dari atas hingga akhirnya terjatuh. Simbol keragu-raguan kepala negara ini berdampak pula pada pilihan-pilihan masyarakat. 299 Ini ditandai, semakin maraknya kegiatan premanisme, seperti geng motor, perampokan di siang hari, pemakaian narkoba dan lain sebagainya. 378 angka penurunan secara kuantitatif dan film-film yang berkualitas pun sulit untuk dapat diproduksi karena bagaimanapun juga untuk melahirkan karya sinematografi yang baik memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Pembajakan karya sinematografi telah membuat banyak perusahaan-perusahaan industri perfilman nasional yang kemudian “gulung tikar”. Hanya film-film yang diputar di media elektronik yang dikenal dengan sinema elektronik (sinetron) yang masih mendapat tempat dalam industri sinematografi itupun karena didukung oleh faktor film cerita sinetron itu sengaja dibuat secara bersambung sehingga pembajakan dapat dicegah dengan sendirinya karena film itu dibuat tidak utuh. 300 Dalam tatanan internasionalpun keragu-raguan pihak eksekutif menyebabkan banyak keputusan-keputusan yang diambil tidak sesuai dengan harapan dan cita-cita negara. Berbagai pertemuan internasional yang melahirkan berbagai-bagai kesepakatan internasional baik itu merupakan perjanjian multilateral maupun perjanjian bilateral dalam banyak kasus disepakati saja tanpa pertimbangan yang masak. 301 Khusus dalam lapangan hak cipta, beberapa peraturan internasional tentang hak cipta yang telah direspon oleh pemerintah pasca penandatanganan GATT 1994/WTO yaitu : 1. TRIPs Agreement (Trade Related Aspects of Property Rights) disahkan melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1994. 2. Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works disahkan melalui Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997. 3. WIPO Copyright Treaty disahkan melalui Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997. 4. Rome Convention 1961 (Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organization (1961). 5. Geneva Convention for the Protection of Producers of Phonograms Againts Unauthorized Deplications of their Phonograms (1971) 6. Brussels Convention Relating to the Distribution of Programme Carrying Signals Transmitted by Satellite (1974). 300 Wawancara dengan Teruna Indra, Pengurus Asosiasi Artis Sinetron Cabang Sumatera Utara tanggal 21 Agustus 2013 jam 11.00 Wib, di Medan. Lihat juga Alberthiene Endah, Panggung Hidup Raam Punjabi, Gramedia, Jakarta, 2005. 301 Dalam kasus ratifikasi GATT/WTO Indonesia telah menambahkan syarat melebihi syarat minimal, lebih lanjut lihat Candra Irawan, Op.Cit. 2011. 379 7. Film Register Treaty (Treaty on the International Registration of Audiovisual Works) (1989) 8. Universal Copyrights Convention 1952. 9. WIPO Performances and Phonogram Treaty (WPPT) disahkan melalui Keputusan Presiden RI N0. 74 Tahun 2004 10. Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1988 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta atas Karya Rekaman Suara antara Negara Republik Indonesia dengan Masyarakat Eropa; 11. Keputusan Presiden RI No.25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat; 12. Keputusan Presiden RI No.38 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Australia; 13. Keputusan Presiden RI No.56 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Inggris; 14. Keputusan Presiden RI N0. 74 Tahun 2004 tentang Pengesahan WIPO Performances and Phonogram Treaty (WPPT); 15. Bejing Treaty on Audivisual Performance ditandatangani di Jenewa, Swiss tanggal 18 Desember 2012 (Indonesia negara ke-53 yang menandatanganinya, akan tetapi Indonesia belum meratifikasinya dalam undang-undang nasional), traktat ini akan berlaku segera setelah 30 negara penandatangan melakukan ratifikasi melalui Undang-undang Nasional negaranya. Kesepakatan-kesepakatan internasional itu menimbulkan konsekuensi secara juridis. Disamping Indonesia diharuskan untuk tunduk pada kesepakatan itu akan tetapi juga hubungan-hubungan internasional yang dilakukan oleh Indonesia akan mengikat secara kelembagaan dengan badan-badan organisasi internasional yang mengelola perlindungan hak cipta itu. Badan-badan organisasi internasional yang mengelola perlindungan hak cipta : 1. World Trade Organization (WTO) membawahi TRIPs Agreement 380 2. United Nation Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) membawahi Universal Copyrights Convention 3. World Intellectual Property Organization (WIPO) membawahi Bern Convention. Jika ditelisik ke belakang selama kurun waktu pemerintahan di Republik ini, kebijakan politik hukum nasional dalam melahirkan undang-undang hak cipta, baru dimulai pada masa pemerintahan orde baru. Pada masa pemerintahan sebelumnya undang-undang hak cipta yang berlaku adalah Auteurswet 1912 Stb. No. 600 peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda. Akan tetapi selama kurun waktu pemerintahan orde baru itu juga, undang-undang hak cipta mengalami perubahan. Perubahan-perubahan itu sejalan dengan perubahanperubahan politik, ekonomi internasional. Matrik di bawah ini menggambarkan perubahan undang-undang hak cipta berdasarkan periodesasi kepemimpinan presiden. Matrik 35 Kebijakan Pembangunan Hukum Hak Cipta Dalam Kurun Waktu Kepemimpinan Presiden No Nama Presiden Periode Kepemimpinan 1. Soekarno 18-08-1945 s/d 19-22-021967 2. Soeharto 22-02-1967 1998 3. Habibie 4. Abdul Rahman Wahid (Gusdur) Megawati 21-05-1998 s/d 20-101999 20-10-1999 s/d 23-072001 23-07-2001 s/d 20-102004 20-10-2004 s/d 2014 5. 6. s/d Susilo Bambang Yudhoyono 7. Joko Widodo 2014 - sekarang Sumber : Diolah dari berbagai sumber 21-05- Produk Undang-undang Hak Cipta Nasional Tidak ada melahirkan Undang-undang Hak Cipta (masih menggunakan UU Hak Cipta Peninggalan Kolonial Belanda, Auterurswet Stb. 1912 No. 600) UU No. 6 Tahun 1982 UU No. 7 Tahun 1987 UU No. 12 Tahun 1997 UU No. 19 Tahun 2002 UU No. 28 Tahun 2014 - Jika dirunut periodesasi perubahan undang-undang hak cipta itu, tampak dengan jelas bahwa pada masa-masa pemerintahan orde baru yang didukung oleh Amerika, perubahan terhadap undang-undang hak cipta itu mengalami percepatan. Selang 5 tahun berlakunya 381 undang-undang No. 6 Tahun 1982, pada tahun 1987, undang-undang hak cipta itu kembali dirobah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1987. Pada tahun 1997 pasca ratifikasi GATT/WTO 1994 Undangundang No. 7 Tahun 1987 itupun kembali dirubah dengan Undangundang No. 12 Tahun 1997. Puncaknya setelah mengalami berbagai tekanan internasional, Undang-undang No. 12 Tahun 1997 pun harus dirubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2002. Pada periode pemerintahan Yudhoyono, menjelang beberapa bulan berakhir masa jabatan kepresidenan beliau, UU No. 19 Tahun 2002 diperbaharui kembali dengan UU No. 28 Tahun 2014 dengan alasan UU No. 19 Tahun 2002 belum mampu menyahuti tuntutan perkembangan yang sedang berlangsung dalam masyarakat dan kami juga mencatat bahwa UU tersebut tidak dapat dijalankan dengan baik, karena kepemimpinan era Yudhoyono penegakan hukum tentang hak cipta tidak efektif disebabkan juga oleh langkah-langkah dan kebijakan yang diambil oleh Yudhoyono cenderung memperlihatkan sikap kepemimpinan yang ragu-ragu. 302 Pelanggaran-pelanggaran hukum yang mungkin akan melibatkan rakyat dalam jumlah yang cukup besar jarang mau dijamah oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum saat ini justru lebih baik memilih posisi-posisi yang aman dan tidak menyibukkan diri dalam urusan yang dapat menyulut kemarahan masyarakat. Situasi ini justru dimanfatkan oleh masyarakat untuk mengambil langkah-langkah yang kadang-kadang bersifat anarkhis. Hasil akhirnya adalah penegakan hukum tenggelam dalam keinginan rakyat yang sebahagian justru dirasuki oleh paham anarkhis. Inilah buah dari pemerintahan eksekutif yang ragu-ragu. Pertanyaannya adalah mengapa pemerintah yang ada hari ini (termasuk pemerintahan pada era sebelumnya) semakin hari semakin besar keragu-raguannya ? Sehinga banyak pihak ingin melakukan reformasi besar-besaran dan bahkan akhir-akhir ini berkumandang pula jargon “restorasi Indonesia” oleh kalangan politisi tertentu yang lainnya mengumandangkan jargon “Perubahan untuk Indonesia” semua mereka ini adalah dari kalangan “oposisi” dengan pemerintahan yang ada pada hari ini. Tulisan inipun tidak akan memberi sumbangan apa-apa dan mungkin hanya meberi sumbangsih sejarah saja untuk kalangan pembaca di masa yang akan datang, jika tidak ada keinginan yang kuat 302 Keragu-raguan ini ditandai dari lambannya Presiden SBY mengambil keputusan yang bersifat strategis seperti kenaikan harga BBM. 382 bagi anak bangsa ini untuk merubah keadaan hari ini kepada keadaan yang lebih baik.303 Persoalan yang penting secara kelembagaan (negara) yang perlu dikemukakan dalam tulisan ini adalah, apakah hukum yang ditempatkan sebagai suatu sistem dalam sistem nasional seperti sekarang ini dapat bekerja dan menyumbangkan sesuatu yang berguna bagi kelangsungan sistem (nasional) itu? Apakah sutu sistem yang di dalamnya terdapat komponen (sub sistem) yang rusak, jika kemudian ditempatkan satu komponen yang baik lalu kemudian komponen yang baik itu bisa menyumbangkan kebaikan pada sistem itu atau justeru ikut rusak? Jika seluruh komponen (sub sistem) sudah rusak, apakah dilakukan metode tambal sulam, dalam arti satu komponen yang rusak satu yang diganti atau kalau semua komponen rusak semua diganti ? Itulah sebuah pertanyaan kegelisahan, ketika melihat keraguan yang besar para penyelenggar negara dalam mengambil keputusan yang sebenarnya berpangkal pada paradigma awal yang telah bermula pada sebauah “paradigma ragu-ragu”. Lihatlah sejarah perjalanan bangsa ini, sekali waktu Bung Karno ingin menjadi Raja dengan “presiden seumur hidup” nya, akan tetapi sebelum ajal menjemputnya ia kemudian diturunkan dari “tahta” sekali waktu Soeharto ingin berkuasa sampai akhir hayatnya, tapi sekali sebelum ajal datang iapun “lengser ke prabon” sekarang ini pun banyak para penguasa eksekutif yang ingin mewarisi kekuasaan eksekutif kepada anak dan cucunya, tidak hanya pada tingkat pemerintah Pusat tapi juga pada tingkat Pemerintah daerah. 304 Inilah buah dari paradigma ragu-ragu para pemimpin dalam pengelolaan manejemen dalam struktur pemerintahan organisasi negara yang belum duduk betul secara sempurna, terutama mengenai bentuk negara. Diskusi tentang pilihan bentuk negara ini telah dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka oleh Bung Hatta, pada pidatonya dalam Deklarasi PNI-Baru tahun 1932. Dalam deklerasi itu Bung Hatta telah memulai gagasan cita-cita otonomi (badan-badan daerah) yang sempurna dan hidup serta dinamis bagi negara Indonesia Merdeka kelak. Pilihan terhadap Pancasila sebagai Dasar Negara dengan Lambang Bhinneka Tunggal Ika, ketika Indonesia berdiri sebagai 303 Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum itu sendiri tidak mau merubahnya. Sesungguhnya kerusakan di bumi dan di langit karena ulah perbuatan manusia itu sendiri. 304 Di Sumatera Utara saja, tidak kurang dari 4 Kepala Daerah Tingkat II, ketika jabatannya berakhir, berupaya untuk mencalonkan anak, isteri atau adiknya menjadi penggantinya. 383 negara yang berdeka, sebenarnya sudah menyahuti cita-cita Federasi itu. PersatuanIndonesia di alam kemerdekaan dengan pluralisme (kebhinnekaan) itu hanya dapat disahuti dengan bentuk negara federal. Sayangnya pada tanggal 18 Agustus ketika UUD 45 disusun justeru norma undang-undangnya yang tidak menyahuti aspirasi itu. Akhirnya bentuk negara terjadilah seperti sekarang ini. Ketika negara Republik Indonesia menanda tangani Perjanjian Renville tanggal 17 Januari 1948 (ibu kota negara masih di Yogyakarta), terbentuklah Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) tanggal 27 Desember 1949, Wali Negara Sumatera Timur dipegang oleh Dr.T.Mansyur. Tapi bentuk negara federal ini mengundang banyak kecurigaan, mengundang banyak prasangka, ini adalah salah satu faktor gagalnya Badan Konstituante (parlemen) untuk menyusun UUD RIS akhirnya tanggal 5 Juli 1959 keluar Dekrit Presiden yang menyatakan kembali ke Undang-undang Dasar 1945. Pernah ada beberapa kali model penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang diundangkan dalam peraturan perundangundangan di Indonesia, yaitu : 1. Pemerintahan di daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Pemerintahan di daerah berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1948 3. Pemerintahan di daerah berdasarkan Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 Tahun 1950 4. Pemerintahan di daerah berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1957. 5. Pemerintahan di daerah berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 1965. 6. Pemerintahan di daerah berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1974 7. Pemerintahan di daerah berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999. 8. Pemerintahan di daerah berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004. Setelah kembali ke UUD 45, bentuk pemerintah di daerah mulai dirancang. Tahun 1974 keluar UU Pemerintahan di Daerah, yakni UU No. 5 Tahun 1974. Istilah-istilah seperti otonomi yang seluas-luasnya, otonomi yang nyata dan seluas-luasnya, otonomi yang bertanggung jawab. Belakangan muncul lagi Undang-Undang Otonomi Daerah No. 22 Tahun 1999 karena dianggap masih belum menyahuti aspirasi direvisi kembali dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan diikuti dengan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang 384 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sekarang ini juga sedang menyeruak tuntutan bagi hasil terhadap hasil Perkebunan yang dikelola oleh BUMN di daerah. Semua ini memperlihatkan kegagalan desain bentuk negara kesatuan dengan sistem otonomi daerah. Kelemahan yang mendasar adalah otonomi daerah seolah-olah hanya menyangkut pembagian kekuasaan Pusat dan Daerah diikuti dengan Keseimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, akan tetapi kering dari perhatian terhadap penyelamatan budaya atau kultur atau nilai-nilai kearifan lokal yang ada di daerah. Kering dari nilai-nilai atau roh atau spirit keadilan antara Pusat dan Daerah. Kekuasan dan keseimbangan keuangan didasarkan pada perhitungan statistik, sedang nilai keadilan tak pernah bisa diukur oleh negeri ini. Nilai kesejahteraan selalu diukur dari penghasilan atau income perkapita, tapi nilai kebahagian tak pernah bisa diukur oleh penyelenggara negara di Republik ini. Tak ada yang tahu betapa bahagianya pencipta tari “serampang dua belas” ketika tariannya ditarikan dan dipelajari oleh banyak orang walaupun untuk kegiatan yang bersifat komersil. Tapi Undang-undang Hak Cipta Nasional hasil produk legislatif menyikapinya secara berbeda. Tidak ada konsep “amalun jariyah” atau konsep “sedhaqoh” dalam undang-undang hak cipta nasional, apalagi dalamTRIPs Agreement, Berne Convention atau Rome Convention. Ada banyak nilai yang hilang, ketika pilihan pardigma bentuk negara itu diawali dari paradigma ragu-ragu. Dampaknya yang muncul dalam perjalanan bangsa ini adalah terjadinya ego sektoral di antara sesama lembaga atau institusi negara yang kemudian terkotak-kotak dalam keegoannya masing-masing. Kerap kali yang terjadi adalah tidak terhubungnya program pembangunan antar Departemen yang satu dengan Departemen yang lain. Kadangkala keadaan ini menimbulkan keraguan baru di kalangan birokrasi untuk mengambil keputusan. Padahal Islam mengajarkan hal yang lebih baik, yakni tinggalkanlah untuk sesuatu yang di dalamnya terdapat keraguan, sebab jika diteruskan akan lebih banyak mudharat daripada manfa’atnya. Itulah yang kata pepatah Melayu “orang gamang mati terjatuh” .Agaknya ketegasan dan kesabaran para pemimpin untuk untuk “menjahit” bahagian yang koyak dan terkotak-kotak dalam struktur pemerintahan menjadi sebuah keharusan. Mestilah ada jalinan kerjasama yang baik antara kementerian Pendidikan dan kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi, dengan Kementerian Keuangan (Bea dan Cukai), dengan Kepolri, 385 Kejagung dengan Organisasi Perfilman Nasional dan lain sebagainya ketika mendudukkan persoalan tentang pembajakan karya sinematografi. Jangan biarkan institusi itu berjalan sendiri-sendiri, karena jika itu yang terjadi semua pihak akan menjadi ragu-ragu dalam mengambil keputusan yang berujung pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan nasional dan pada saat bersamaan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di negeri ini. D. Budaya Penegakan Hukum Pemaknaan terhadap budaya hukum selalu dicari melalui akar katanya yakni budaya dan hukum. Budaya selalu pula dikonsepkan secara sempit. Dalam studi-studi antropologi budaya sering juga dirumuskan sebatas sistem lambang, sistem material dan sistem sosial selalu dilepaskan dari konsep budaya meskipun sesungguhnya antara sistem material dan sistem sosial selalu ada hubungan yang saling berkaitan, berjalin, berkelindan dalam satu sistem lambang. 305 Akan tetapi dalam pandangan yang terintegral atau holistik budaya selalu dikonsepkan sebagai sistem makna dan sistem nilai yang diletakkan dalam lapis dan basis mental. Lapis dan basis mental adalah bahagian yang terdalam dari sebuah budaya karena dimensi terdalam budaya terdapat pada nilai yang melekat di dalamnya. 306 Sebagai suatu sistem nilai (system of value) budaya akan melahirkan ide-ide normatif sedangkan sebagai suatu sistem makna (system of meaning) budaya akan melahirkan ide-ide kognitif. Keduanya melekat dan saling tidak terpisahkan (inheren) pada budaya sebagai sistem lambang dan secara serempak membangun dunia secara berulang-ulang (the symbolic system make and remake the world). 307 Koentjaraningrat 308 memberikan batasan bahwa hampir seluruh aktivitas manusia adalah kebudayaan kecuali perilaku refleks 305 Lebih lanjut lihat Harsya W. Bachtiar, Sistem Budaya Indonesia, Budaya dan Manusia di Indonesia, Hanidita, Yogyakarta, 1985, hal. 67. 306 Lebih lanjut lihat Ignas Kleden, Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan, LP3ES, Jakarta, 1987, hal. 17. Lihat juga Kathleen Newland dan Kemala Candrakirana Soedjatmoko, Menjelajah Cakrawala, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hal. 95. 307 Lebih lanjut lihat Paul Ricour, dalam Mario J. Valdes (ed), Reflection and Imagination : A Ricour Reader, Harvester Wheatsheaf, New York, 1991, hal. 117. 308 Koetyaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Aksara Baru, Jakarta, 1986, hal. 180-181. Lihat juga Koetyaraningrat, Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan, PT. Gramedia, Jakarta, 1987, hal. 12. 386 yang didasarkan pada naluri yang tidak dikategorikannya sebagai kebudayaan. Ia membagi 3 wujud kebudayaan : Pertama, wujud kebudayaan berupa kompleksitas ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan yang merupakan wujud ideal dan sifatnya abstrak. Kedua, wujud yang berupa kompleksitas aktivitas perilaku yang terpola dari manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, wujud yang berupa benda-benda hasil karya manusia yang bersifat konkrit atau nyata. Bertolak dari konsep kebudayaan yang diuraikan di atas, jika dihubungkan dengan hukum maka sebenarnya, hukum adalah merupakan sub sistem dari budaya karena hukum tidak hanya berisikan gagasan, ide-ide dan nilai-nilai akan tetapi juga secara nyata (empirik) hukum juga merupakan kompleksitas dari perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. 309 Hukum merupakan konkritisasi dari nilainilai budaya yang dihasilkan dari berbagai interaksi dalam kehidupan bermasyarakat. Wujudnya dapat dalam bentuk gagasan-gagasan tentang keadilan, tentang persamaan dapat juga dalam bentuk kitab undangundang, putusan hakim, dalam bentuk kebiasaan-kebiasaan serta dalam bentuk doktrin hukum. Oleh karena itu dimanapun ada masyarakat di dunia ini didalamnya pasti ada hukum (ubi sosietes ibi ius) sebagai hasil dari kebudayaan. Jika mau dikelompokkan hukum termasuk dalam budaya immateril. Konsekuensi terhadap hukum yang merupakan produk kebudayaan akan memunculkan apa yang disebut dengan relativitas budaya. Berdasarkan konsep ini, hukumpun akan mengikuti kenyataan jika masyarakat yang akan melahirkan kebudayaan itu bersifat plural maka nilai-nilai normatif yang dianut juga akan bersifat plural. Karena itu hukum sering tidak mempunyai kekuatan berlaku secara universal. Pilihan-pilihan hukum selalu ditentukan tempat di mana hukum itu diberlakukan. Yang oleh Donal Black disebutnya bahwa keberlakuan hukum sangat ditentukan oleh keadaan disekitar atau yang mengelilingi norma hukum itu diberlakukan. 310 309 Uraian-uraian tentang ini lebih lanjut lihat T.O. Ihromi, Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993. Bandingkan juga dengan Soerjono Soekanto, Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial, Rajawali, 1988, hal. 164. 310 Lebih lanjut lihat Donald Black, Sociological Justice, Oxford University Press, New York, 1989. 387 Oleh karena itu tiap-tiap perilaku stakeholders dalam praktek penegakan hukum adalah merupakan budaya hukum mulai dari perilaku legislatif ketika hukum itu dibuat, prilaku birokrasi atau budya eksekutif yang mengintervensi lembaga legislatif dan judikatif, sampai pada perilaku yudikatif sebagai lembaga penegak hukum dan perilaku masyarakat sebagai pemegang peran terhadap aktivitas penegakan hukum. 1. Budaya Hukum Legislatif Jika dirujuk pada fungsi dan tugas serta kewenangan lembaga legislatif dalam UUD 45 (baik sebelum atau sesudah amandemen), sebenarnya sudah tertera secara nyata. Di samping sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi nasional, tapi kepadanya juga diberikan fungsi pengawasan yang disebut dengan pengawasan legislatif. Keduukan yang demikian menyebabkan legislatif mempunyai “kekuasaan” yang sangat besar dalam pengelolaan kehidupan nasional sebagai peneyelenggara tugas-tugas yang diembankan kepadanya. Jika dirujuk pada fungsi dan tugas serta kewenangan lembaga legislatif dalam UUD 45 (baik sebelum atau sesudah amandemen), sebenarnya sudah tertera secara nyata. Di samping sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi nasional, tapi kepadanya juga diberikan fungsi pengawasan yang disebut dengan pengawasan legislatif. Keduukan yang demikian menyebabkan legislatif mempunyai “kekuasaan” yang sangat besar dalam pengelolaan kehidupan nasional sebagai peneyelenggara tugas-tugas –tugas yang diembankan kepadanya. Sebenarnya jika semuanya sudah jelas ada dalam UU tentang semua aktivitas yang akan dilakukan oleh anggota legislatif itu, maka pada galibnya tak ada lagi prilaku budaya yang perlu didiskusikan. Tiap-tiap penyimpangan dalam tugas dikenakan sanksi hukum dan lembaga itu dapat berperan sesuai dengan cita-cita penegakan hukum ketika UU tentang Fungsi ,peranan dan kewenangan lembaga legislatif itu disusun. Akan tetapi dalam tataran praktek tak sedikit juga kritik terhadap lembaga ini, baik secara kelembagaan maupun secara perorangan yakni individu yang dalam kesehariannya duduk sebagai anggota lembaga itu. Kritik-kritik itu mulai dari perebutan pimpinan, perlu tidaknya menggunakan hak interpelasi untuk berbagai kasus kenegaraan, urusan delegasi, calo anggaran sampai pada biaya rehabilitasi gedung dan ruang rehat dan kamar mandi Gedung DPR-RI yang menghabiskan dana ratusan miliar rupiah. Issu-issu itu semuanya terpaut dengan 388 kultur legislatif yang sudah “mendarah daging” di lembaga itu. Bekerja dengan penghasilan yang tinggi, namun sedikit sekali hasil kerja mereka yang memberikan manfaat bagi kepentingan negara. Waktu mereka lebih banyak terbuang untuk kepentingan pribadi mereka, terutama ketika melakukan studi perbandingan di luar negeri.311 Kinerja DPR-RI sebagai lembaga negara tak ubahnya seperti kinerja Organisasi kemasyarakatan pemuda atau mahasiswa, bahkan kadang-kadang lebih terlihat profesional organisasi pemuda dan mahasiswa itu yang tak pernah jelas sumber anggaran dan biaya organisasinya. Pada saat era sekarangpun dapat dibuktikan bagaimana kinerja anggota DPR-RI dalam berbagai rapat paripurna. Bolos atau tidak hadir dalam berbagai kegiatan rapat itu adalah persoalan biasa. Baru dianggap sebuah berita besar jika anggota DPR-RI terlibat korupsi atau skandal moral. Padahal urusan wajib hadir saja tak bisa mereka penuhi.312 Sulit untuk diharapkan pada masa-masa yang akan datang, badan yang dipercaya untuk menjalankan misi politik hukum ke depan mampu mempertahankan, memperjuangkan dan memasukkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang merupakan pencerminan dari harapanharapan masyarakat yang tersimpul dalam The Original Paradicmatic Values of Indonesia Culture and Society. Anggapan ini semakin menguat ketika sebahagian dari anggota legislatif yang tidak mampu mengemban amanah rakyat. Bahkan secara terang-terangan telah melakukan aktivitas pelanggaran hukum. Matrik di bawah ini telah membuktikan, betapa perilaku para anggota DPR-RI tidak jauh berbeda dengan perilaku anggota masyarakat biasa. Matrik 36 Matrik Pelanggaran Hukum Yang Dilakukan oleh Anggota Legislatif DPR-RI No 1. 2. Jabatan Di DPR-RI Anggota DPRRI Anggota ZD Fraksi di DPR-RI (Asal Partai) PPP LH PKS Inisial Nama Kasus yang Dilanggar Korupsi Pengadaan Qur’an Depag Import daging sapi Al- 311 Banyak kritik dari kalangan mahasiswa Indonesia di luar negeri, ketika anggota DPR RI berkunjung ke sana. Mereka lebih banyak pelesiran, shopping dan sedikit sekali melakukan aktivitas yang berguna bagi kepentingan bangsa 312 Lihat lebih lanjut Koran Sindu, 16 Mei 2013. 389 3. Komisi I DPRRI Anggota DPRRI Anggota DPRRI MN Demokrat NAR PAN Anggota DPRRI Ketua Komisi IV DPR AS Demokrat 7. Anggota DPRRI AC 8. Anggota RI Anggota RI Anggota RI Anggota RI Anggota RI DPR- HI DPR- FAL DPR- AAN DPR- ST DPR- AC PDIP Kasus Hambalang, Suap Wisma Atlet Kasus Hambalang, Kasus Suap Pembangunan Gedung Pusdiklat Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) Kasus Hambalang, Kasus Suap Wisma Atlet Alih fungsi hutan lindung dan pengadaan SKRT Dephut Alih fungsi hutan lindung dan pengadaan SKRT Dephut Suap dalam kasus Anggoro Wijoyo Suap dalam kasus Anggoro Wijoyo Tindak pidana korupsi alih fungsi hutan lindung Suap dalam pengembangan Pelabuhan Tanjung Api-api Suap (Cek Pelawat) Anggota RI Anggota RI Anggota RI Anggota RI Anggota RI Anggota RI Anggota RI Anggota RI Anggota RI Anggota RI Anggota RI DPR- HY BA Golkar Golkar Suap (Cek Pelawat) Suap (Cek Pelawat) DPR- AZA Golkar Suap (Cek Pelawat) DPR- AHZ Golkar Suap (Cek Pelawat) DPR- BS Golkar Suap (Cek Pelawat) DPR- PZ Golkar Suap (Cek Pelawat) DPR- HB Golkar Suap (Cek Pelawat) DPR- RK Golkar Suap (Cek Pelawat) DPR- ARS Golkar Suap (Cek Pelawat) DPR- AM Golkar Suap (Cek Pelawat) DPR- TMN Golkar Suap (Cek Pelawat) DPR- MBS Golkar Suap (Cek Pelawat) 4. 5. 6. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. EF PPP 390 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Anggota RI Anggota RI Anggota RI Anggota RI DPR- NDAJS PPP Suap (Cek Pelawat) DPR- UFH PPP Suap (Cek Pelawat) DPR- DT PPP Suap (Cek Pelawat) DPR- SU PPP Suap (Cek Pelawat) Anggota RI Anggota RI Anggota RI Anggota RI Anggota RI Anggota RI Anggota RI Anggota RI Anggota RI Anggota RI Anggota RI Anggota RI Anggota RI Anggota RI Anggota RI Anggota RI Anggota RI Anggota RI Anggota RI Anggota RI DPR- DMM PDIP Suap (Cek Pelawat) DPR- WT PDIP Suap (Cek Pelawat) DPR- SP PDIP Suap (Cek Pelawat) DPR- ACP PDIP Suap (Cek Pelawat) DPR- MI PDIP Suap (Cek Pelawat) DPR- B PDIP Suap (Cek Pelawat) DPR- PS PDIP Suap (Cek Pelawat) DPR- AS PDIP Suap (Cek Pelawat) DPR- RL PDIP Suap (Cek Pelawat) DPR- MM PDIP Suap (Cek Pelawat) DPR- JTL PDIP Suap (Cek Pelawat) DPR- MP PDIP Suap (Cek Pelawat) DPR- EP PDIP Suap (Cek Pelawat) DPR- SHW PDIP Suap (Cek Pelawat) DPR- NLMT PDIP Suap (Cek Pelawat) DPR- S PDIP Suap (Cek Pelawat) DPR- PN PDIP Suap (Cek Pelawat) DPR- SHW PDIP Suap (Cek Pelawat) DPR- ZEM PDIP Suap (Cek Pelawat) DPR- UD TNI/Polri Suap (Cek Pelawat) 391 49. 50. 51. 52. Anggota RI Anggota RI Anggota RI Anggota RI DPR- RS TNI/Polri Suap (Cek Pelawat) DPR- S TNI/Polri Suap (Cek Pelawat) DPR- DY TNI/Polri Suap (Cek Pelawat) DPR- IWK PDIP Kasus Suap Wisma Atlet Kasus Korupsi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Kasus Suap Dermaga 53. Anggota DPRRI WON PAN 54. Anggota DPRRI Anggota DPRRI AHD PAN BR PBR Anggota DPRRI Anggota DPRRI SU Kasus Suap Proses Lelang Pengadaan Kapal Patroli Dephub Kasus Suap APBN Batam Golkar Kasus Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran (Damkar) 55. 56. 57. SD Sumber : Diolah dari berbagai sumber Matrik di atas memberikan keyakinan kepada siapapun bahwa nilai-nilai sakral yang seharusnya dijaga oleh anggota legislatif tidak lagi menjadi bahagian yang penting untuk dipelihara. Peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi sepanjang karir mereka sebagai anggota legislatif dilakukan tanpa pertimbangan hati nurani. Peranan legislatif dalam kebijakan legislasi tak sekedar bergeser dari menjustifikasi kekuasaan eksekutif (khususnya pada masa orde pemerintahan Soekarno dan Soeharto) tapi kemudian pada era pemerintahan pasca Soeharto telah bergeser menjadi jabatan prestise yang dapat dijadikan sebagai ajang untuk memperkaya diri sendiri. Ideologi Pancasila tak mampu lagi membentengi prinsip-prinsip kerja mereka yang telah dirasuki oleh ideologi materialis. Ideologi yang disebut terakhir inilah kemudian yang mengantarkan mereka pada pilihan-pilihan hedonisme yang berujung pada pelanggaran hukum. Karya-karya akademis para intellektual di negeri ini sudah bertumpuk-tumpuk yang isinya mengeritik berbagai kebijakan di negeri ini yang mempertontonkan ego institusional atau ego sektoral. Antara institusi atau departemen atau sekarang ini menggunakan istileh 392 kementerian tidak memperlihatkan kerja sama yang sistemik. Antara institusi negara yang satu dengan yang lain, seakan-akan sedang mengikuti perlombaan untuk berebut menjadi sang juara. Di sinilah kemudian menjadi teramat penting gagasan yang selalu didengungkan oleh M.Solly Lubis.313 Pembangunan apapun yang hendak dibangun di negeri ini, politik, ekonomi, pertahanan keamanan, sosisal budaya (termasuk hukum di dalamnya) harus mengacu pada manajemen sistem pembangunan nasional. Semua aktivitas pembanbangunan nasional harus dapat diukur dan diuji serta dirujuk untuk kemudian ditempatkan dalam sistem nasional. Tidak boleh ada yang keluar dari sistem nasional. Keluar dari sistem nasional, berarti keluar dari organ tubuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuatu yang berada di luar sistem tidak boleh ikut menentukan bekerja dan berjalan sebuah sistem. Sebuah sistem harus bekerja secara simultan dan menghendaki sebuah kekompakan. Semua komponen dalam sistem harus bekerja secara bersama-sama untuk terwujudnya tujuan sebuah sistem. Seumpama mesin kenderaan, komponen seperti, karburator, busi, platina, sokar, peston, ring peston, radiator dan sil (benda kecil terbuat dari bahan karet) harus bekerja bersama-sama untuk menghasilkan energi mekanik yang dapat menggerakkan roda setelah dihubungkan melalui geer, gardang dan roda. Semua komponen mesin kenderaan itu (sub sistem) saling bekerja, tidak ada klaim komponen yang satu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari yang lainnya. Sil atau ring peston sekecil apapun dan semurah apapun tetaplah mempunyai kedudukan yang sama pentingnya dengan peston atau radiator. Begitulah ketika sebuah mesin bekerja, masing-masing komponen atau subsistem tidak lagi bergantung pada kedudukannya, tapi bekerja sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing dan saling kait mengait satu sama lain memberikan energi dan sumbangan tenaga sesuai dengan fungsinya. Kerjasama yang saling kait mengait adalah sebuah keharusan dalam bekerjanya sebuah sistem. Mengacu pada contoh bekerjanya sistem mesin tersebut, maka dalam sebuah negarapun masing-masing susb sistem atau elemen negara harus saling bekerjasama dalam arti menyumbangkan energi sesuai fungsi dan kedudukannya. Tiap-tiap kementerian sebagai sub sistem elemen negara mempunyai fungsi dan tugasnya masing-masing. Fungsi dan tugas itu bila dijalankan akan menghasilkan energi, akan 313 Lebih lanjut lihat M. Solly Lubis, Manajemen Strategis Pembangunan Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2011. 393 tetapi energi itu belum tentu akan dapat menyumbangkan sesuatu yang terbaik dalam mencapai tujuan negara, bila tidak dihubungkan dengan komponen sistem (baca : kementerian) yang lain. Bagaimana upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bisa dicapai kalau kemudian untuk mendapatkan buku bacaan berkualitas yang berasal dari luar negeri dikenakan “pajak barang mewah” hanya karena buku itu harganya lebih dari Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) per eksemplar (per satu buku). Ini menunjukkan Kementerian Pendidikan Nasional tidak bekerja bersama-sama dalam satu sistem dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan cq.Direktorat Jenderal Pajak. Mampukah bangsa ini mengimbangi investasi asing di negeri Vietnam atau Cina dalam menarik investor, jika hukum tentang HKI nya tak pernah dikordinasikan pembuatannya dengan Badan Penanaman Modal Asing atau kementerian Investasi? Terlalu jauh dari harapan untuk mendudukkan dalam satu forum diskusi yang intensif dalam rangka merumuskan politik hukum HKI yang melibatkan institusi legislatif atau Balegnas, Kementerian Kehakiman, kementerian Keuangan dengan Kementerian Penanaman Modal untuk sebuah undang-undang Hak Cipta. Masing-masing kementerianpun masih dibebani oleh beban tugasnya masing-masing. Yang terjadi di kemudian hari adalah, undang-udang yang dilahirkan tidak menunjukkan komitmen yang kuat guna mewujudkan tujuan negara. Kecongkakan sektoral sebagai wujud pengangkangan dari ide dan gagasan membangun negara harus berada dalam satu wadah yang disebut sebagai sistem nasional, akhirnya membuahkan hasil di mana capai dari pembangunan nasional itu kehilangan benang merahnya. 314 Mengapa semua arus gerak pembangunan setelah lebih dari 67 tahun merdeka menjadi tidak terukur ? Mengapa lembaga institusi legislatif dan anggota DPR RI tidak juga memperlihatkan kedewasaannya ? Semua ini sebenarnya tidak terlepas dari pengalaman pemerintahan masa lalu yang kurang memberi makna pada sistem pemerintahan dan organisasi modern yang disebut negara. 315 314 Sulit untuk diukur keberhasilan PT.Telkom (Persero) membangunan jaringan telepon dengan keberhasilan pihak Jasa Marga dalam membangun jalan. Sulit diukur keberhasilan Dinas Pertamanan dalam memperindah dan mempercantik kota dengan keberhasilan pihak Perusahaan Daerah Air Minum dalam pemenuhan kebutuhan jaringan air bersih yang harus disalurkan ke pemukiman atau rumah-rumah penduduk. 315 Era pemerintahan Bung Karno dan Soeharto, tampaklah bahwa UUD 1945 itu mudah diselewengkan dengan berbagai penafsiran. Pancasila-pun begitu mudah diberi makna untuk menjastifikasi kekuasaan. Kepemimpin Soeharto yang begitu kuat dengan tradisi dan doktrin militernya, telah membentuk budaya legislatif yang korup, setelah lebih dari 3 dasawarsa menyelimuti “gedung Senayan”. Siapa mereka di Senayan pada 394 2. Budaya Hukum Eksekutif Penegakan hukum yang selektif atau penegakan hukum yang “tebang pilih” sudah lama menjadi perbincangan di negeri ini. Sejarah penegakan hukum di negeri ini tidak pernah luput dari pergunjingan tentang adanya “mafia peradilan”. Intervensi pihak eksekutif dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan “kaum birokrat” apalagi yang sedang berkuasa tak pernah dapat dihilangkan sejak zaman orde baru hingga hari ini. Dalam sebuah wawancara dengan advokad ternama di Kota Medan 316 beliau mengatakan : Sampai hari ini saya beracara di berbagai tingkat Pengadilan tak pernah luput dari transaksi. Transaksi itu tidak hanya menyangkut perkara perdata untuk dapat dimenangkan, tapi juga dalam kasus pidana, terutama tindak pidana korupsi. Khusus untuk perkara pidana transaksi mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai tingkat pemeriksaan di Pengadilan. Itu artinya, mulai polisi, jaksa sampai hakim dapat dibayar dan pernah menerima pembayaran dari klien kami. Tidak ada yang dapat ditutupi lagi. Mafia peradilan itu nyata adanya. Tidak hanya dalam kasus yang berada dalam posisi “salah” untuk kasus yang berada pada posisi “benar” pun diharuskan juga untuk membayar, jika tidak , yang benarpun akan jadi salah. Itulah sebabnya orang begitu “alergi” berurusan dengan lembaga peradilan. Dalam banyak hal selalu muncul pertanyaan, mengapa untuk kasus yang tertentu orang tidak memilih jalur peradilan, jawaban yang selalu diperoleh adalah, “perkara yang diperjuangkan nilainya seekor harga kambing, tapi kalau ditempuh jalur pengadilan, biaya yang dikeluarkan sama nilainya dengan seekor lembu”. Hikmahanto Juwana 317 menyebutkan penegakan hukum yang diwarnai dengan uang merupakan satu problem yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum. Lebih lanjut beliau mengatakan : Di setiap lini penegakan hukum, aparat dan pendukung aparat penegak hukum, sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktek korupsi atau suap. Uang dapat berpengaruh pada saat polisi melakukan penyidikan perkara. masa itu ? Golkar, PDI dan PPP adalah “Soeharto”. Semua tunduk pada keinginan rezim yang berkuasa pada waktu itu. Agaknya sulit untuk melepaskan pengalaman masa lalu yang sudah terpatri selama puluhan tahun itu. Jika hari ini terlihat sepertinya ada perubahan, akan tetapi dalam praktek yang berubah hanya subyeknya saja, prilakunya tetap menampilkan warna-warni legislatif masa lalu itu. 316 Wawancara dengan AHS, tanggal 12 September 2012, pukul 10.00 WIB di Medan. 317 Lihat lebih lanjut, Hikmahanto Juwana, Penegakan Hukum Dalam Kajian Law and Development : Problem dan Fundamen Bagi Solusi di Indoensia, Pidato Ilmiah, Disampaikan pada Acara Dies Natalis Ke-56 Universitas Indonesia, Kampus UI Depok, 4 Februari 2006, Op.Cit, hal 15. 395 Dengan uang, pasal sebagai dasar sangkaan dapat diubah-ubah sesuai jumlah uang yang ditawarkan. Pada tingkat penuntutan, uang bisa berpengaruh terhadap diteruskan tidaknya penuntutan oleh penuntut umum. Apabila penuntutan diteruskan, uang dapat berpengaruh pada seberapa berat tuntutan yang akan dikenakan. Dalam banyak kasus keterlibatan lembaga eksekutif dalam intervensi di lembaga peradilan telah berlangsung lama, mulai dari tingkat daerah sampai di tingkat Pusat. Proses penegakan hukum untuk kalangan birokrasi pemerintahan kelihatannya sudah dikavling. Untuk perkara-perkara tingkat kelurahan, disidik oleh Polsek, perkara-tingkat kecamatan disidik oleh Polresta sedangkan perkara untuk tingkat Pemerintah Kota atau Kabupaten dan Propinsi disidik oleh Polresta atau Polda tergantung nilai nominal dan jenis kejahatannya. Jika nilai korupsinya ratusan miliar, perkara ini bisa diambil alih oleh Polri. Hal yang sama juga berjalan secara simetris dengan pihak Kejaksaan. Sehingga tidak heran jika suatu perkara dapat diendapkan bertahuntahun, tergantung bagaimana kepiawaian para pemimpin birokrasi di tataran eksekutif itu melakukan loby. Para aparat penegak hukum itu seakan-akan mengetahui jumlah transaksi dengan menghitung “nilai perkara” atau kekayaan para pejabat yang korupsi itu. Ada semacam kesepakatan tidak tertulis diantara mereka berapa jumlah yang akan ditransaksikan, sehingga “bagi-bagi” hasil korupsi menjadi seimbang. 318 Perkara-perkara yang digelar di Pengadilan baik itu perkara pidana, perdata atau TUN sebahagian besar sarat dengan muatan mafia hukum, akan tetapi tidak semua demikian. Dalam sebuah wawancara dengan SY319 seorang advokad senior yang memiliki talenta berperkara yang handal, mengatakan ; Selama lebih dari 24 tahun beracara, tidak semua perkara yang saya pegang mengandung unsur mafia hukum atau transaksional. Khusus untuk kategori klien miskin atau menengah ke bawah itu rata-rata saya menangkan tanpa transaksional. Di samping tidak ada yang ditransaksikan, para klien itupun biasanya datang dengan kejujuran dan kebenaranan, sehingga pihak kita selalu berada di pihak yang benar. Tapi untuk perkara-perkara yang melibatkan kelompok ekonomi menengah atas, dan masuk dalam perkara “besar” atau dengan nilai ekonomi yang tinggi, perkara itu dimenangkan dengan hitungan fifty-fifty. Artinya 50 % dengan transaksional, 50 % murni tanpa transaksional. 318 Oksidelfa Yanto, Mafia Hukum Membongkar Konspirasi dan Manipulasi Hukum di Indonesia, Penebar Swadaya, Jakarta, 2010. 319 Wawancara, di Medan, tanggal 18 Feberuari 2013, pukul 16.00. 396 Menurut SY, mafia hukum masih ada dan akan terus ada, akan tetapi tidak semua perkara dilakukan secara transaksional, jika ada keyakinan bahwa klien nya berada di pihak yang benar dan memungkinkan untuk dapat dimenangkan, maka transaksional tuidak dilakukan. Akan tetapi ada juga perkara yang dia yakini benar, namun karena nilainya “besar” jika tidak ditempuh dengan cara transaksional, dikhawatirkan bisa “kalah” maka cara transaksional juga akan ditempuh, sebagaimana diungkapkan oleh SY. 320 Kalau kita yakin menang, kita tidak akan lakukan cara transaksional, tapi kalu ragu bisa meang, atas permintaan klien, praktek transaksional baru akan kita lakukan. Ada juga perkara yang kita yakin menang, tapi karena nilainya besar, dan jika tidak dikeluarkan dana sedikit kita bisa dikalahkan, maka cara transaksional akan dilakukan. Itupun dilakukan atas permintaan klien. Faktor kekhawatiran akan dikalahkan oleh pihak peradilan, ternyata berpengaruh pada pilihan untuk melakukan cara transaksional. Transaksional itu dilakukan dengan menggunakan orang-orang yang dipercaya, di lembaga penegakan hukum itu. Untuk perkara yang realatif bernilai ekonomi rendah, transaksional dapat dilakukan dengan menggunakan personil penyidik, tapi untuk perkara di tingkatkan pemeriksaan tingkat pengadilan, transaksional dapat dilakukan dengan menggunakan personil panitera di lembaga peradilan itu, sedangkan untuk perkara yang “besar” biasanya menggunakan pihak ketiga, seperti yang diungkapkan SY 321 dalam wawancara berikut ini : Praktek transaksional itu biasanya kalau di pengadilan menggunakan panitera, kalau di tingkat kepolisian menggunakan juper sama juga di kejaksaan . Kalau untuk tingkat perkara besar, menggunakan calo, biasanya pihak ketiga. Praktek-praktek transaksional itu ada juga yang melibatkan antar lembaga, untuk perkara-perkara korupsi di berbagai instansi. Biasanya praktek transaksional itu dilakukan dengan “rapi” dan penasehat hukum atau kuasa hukum hanya digunakan sebagai pihak yang menyiapkan prosedur formal menurut hukum acara dan melengkapi substansi perkara sesuai persyaratan formal di lembaga peradilan, seperti yang di ungkapkan oleh SY 322 berikut ini : Biasanya untuk perkara antar lembaga yang melibatkan instansi pemerintah transaksional dilakukan oleh dengan menggunakan pihak ketiga dan kami selaku kuasa hukum hanya menyediakan saja substansi hukum yang diperlukan dan dilaksanakan sesuai hukum acara, finalisasi untuk perkara itu 320 Ibid. Ibid. 322 Ibid. 321 397 dapat dimenangkan atau tidak, diserahkan sepenuhnya pada pimpinan lembaga atau antar pimpinan lembaga itu dengan lembaga peradilan. Praktek-praktek transaksional inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor penyebab sehingga perkara-perkara pelanggaran hukum hak cipta, menjadi persoalan yang tidak menarik. Dalam wawancara dengan SY 323 terungkap bahwa setelah lebih dari 24 tahun beracara, beliau tak pernah menangani kasus pelanggaran hak cipta, seperti ungkapannya berikut ini : Tak pernah ada permintaan klien tentang kasus pelanggaran hak cipta. Menurut saya faktor penyebab mengapa persoalan hak cipta tidak menjadi perhatian aparat penegak hukum karena hal ini menyangkut budaya. Budaya kita belum sampai ke sana, sebab yang menjadi korban terhadap pelanggaran hak cipta hanya segelintir orang. Belum mengganggu hajat hidup orang banyak. Disamping pentingnya arti perlindungan hak cipta belum tersosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Dalam aspek penegakan hukum kesiapan aparat penegak hukum juga berpengaruh pada pilihan terhadap penanganan perkara hak cipta, demikian juga secara struktural aspek kelembagaan dan pendanaan juga tidak dapat dilepaskan, pendek kata mulai dari sikap mental aparat penegak hukum sampai pada kemauan untuk menegakkan hukum hak cipta itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saat ini penanganan perkara pada tingkat penyidikan masih menganut sistem tebang pilih. Hanya saja prinsip tebang pilihnya tidak melihat urgensinya, tapi melihat pada besaran nilai perkaranya secara ekonomi. Untaian wawancara tersebut, mengantarkan tulisan ini pada satu preposisi bahwa mafia peradilan itu memang nyata-nyata ada. Budaya korup pada tingkat birokrasi (eksekutif) diteruskan distribusinya kepada lembaga judikatif. Ketika para birokrat (eksekutif) melakukan perbuatan melawan hukum atau Tindak Pidana, aparat penegak hukum melakukan aktivitas penegakan hukum. Langkah berikutnya para advokat atau penasehat hukum tampil sebagai mediator dan membicarakan langkah-langkah “penyelesaian” di luar hukum. Mengenai jumlah atau besaran transaksi akan diputus antara pimpinan lembaga. Jika sudah ada kesepakatan, putusan yang diambil beragamberagam , sebagaimana diungkapkan oleh AHS. 324 Kalau sudah ada kesepakatan putusan yang diambil bermacam-macam. Jika perkara itu masih tingkat lit (maksdunya penelitian), perkaranya tidak jadi diteruskan. Tetapi jika perkaranya sudah masuk ketingkat Dik (penyidikan) perkara itu bisa dihentikan (SP3). Jika perkaranya sudah disidangkan, loby dilakukan di kedua lembaga yakni Kejaksaan dan Pengadilan. Tuntutan bisa 323 324 10.12. Ibid. Wawancara tanggal 3 Maret 2013,dengan AHS advokat di Medan pukul 398 diperkecil, sehingga hakim bisa hukumannya menjadi ringan. membebaskan atau kalau diputus Jika demikian halnya mafia peradilan itu berpotensi untuk perkara-perkara yang bernilai ekonomis. Untuk perkara-perkara yang tidak memiliki nilai ekonomis, praktis tak menjadi ranah mafia peradilan. Namun sayangnya, aparat penegak hukumpun enggan untuk menjamahnya, apalagi dalam struktur perkara itu tidak ada melibatkan unsur pimpinan birokrasi. Sebut saja misalnya dalanm perkara pembajakan atau pelanggaran hak cipta, kasus ini tidak menjadi perhatian yang menarik kalangan aparat penegak hukum. Meminjam istilah Mahadi hukumnya ada, aparat penegak hukumnya ada, pelanggaran hukumnyapun nyatanyata ada,tapi hukumnya tak tegak, masih tergolek. Seumpama batang kayu kata, Mahadi 325 hukum itu memang dapat ditegakkan, dapat diberdirikan, akan tetapi saat ini batang kayu itu masih tergolek, masih tertidur. Pandangan Mahadi ini melukiskan suatu keadaan bahwa secara substansi hukumnya ada, materi hukumnya cukup, akan tetapi masih berada di dalam Kitab Perundangundangan, atau kalau hukumnya tak tertulis, materi hukumnya ada tetapi masih tersimpan di hati sanubari masyarakat. Sasaran yang hendak dijelaskan oleh Mahadi adalah profesionalisme aparatur penegak hukum. Kekuatan untuk mendirikan batang yang tergolek itu, batang yang tergeletak itu berada di tangan aparatur penegak hukum. Yang tergolek dapat ditegakkan. Hukum yang tertidur dapat dibangunkan. Bahkan menurut Mochtar Kusumaatmadja,326 hukum dapat merubah perilaku masyarakat, dapat dijadikan alat untuk merubah masyarakat. Menjadi “tool” menjadi jalan, menjadi faktor pengubah yang dominan (variabel independent) untuk merubah, membentuk atau mengarahkan (engeneering) masyarakat (variabel dependent) sesuai kemauan hukum yang telah di desain untuk kepentingan perubahan itu. Mendesain hukum untuk sebuah kepentingan itulah politik hukum. Politik yang digunakan untuk menata sistem kehidupan nasional dalam suatu negara. Dalam sistem nasional terdapat berbagai-bagai komponen yang merupakan sub sistem meliputi: sub sistem politik, ekonomi, hukum dan keamanan serta 325 Materi Kuliah Mahadi pada Program Pascasarjana USU (KPK-UGM USU), 1993-1994. 326 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni, Bandung, 2002. 399 sosial-budaya seperti yang digambarkan oleh M. Solly Lubis. 327 Hukum hanya satu komponen saja (sub sistem) dalam sistem sosial yang lebih luas (sistem nasional). Tak dapat tidak, begitu ungkapan beliau, apa yang terjadi pada sub sistem sosial lainnya, akan berpengaruh pada sub sistem hukum dalam sistem nasional. Hukum tidak berada pada ruang hampa, demikian kata Satjipto Rahardjo,328 tapi berada pada ruangan yang telah berisi dengan berbaga-bagai pernak-pernik budaya, perilaku dan sering kali bersitegang akibat terjadi kekuatan tarik menarik (baik karena desakan faktor ekonomi maupun karena berisikan tekanan faktor politik) dalam praktek penegakannya. Berpikir untuk menegakkan hukum, tidaklah dapat dilakukan berdasarkan cara pandang linier. 329 Terdapat banyak faktor non linier yang turut bekerja atau turut mempengaruhi penegakan hukum. Berpikir linier dalam praktek penegakan hukum sama artinya menjadikan manusia dan masyarakat seperti robot dan bekerjanya masyarakat seperti mesin. Hitungan-hitungannya tunduk pada logika ilmu fisika dan logika matematika. Penegakan hukum dalam bidang karya sinematografi tidak dapat didasarkan dan diukur melalui logika linier. Undang-undang No. 19 Tahun 2002 hanya mampu menuangkan norma-norma perlindungan hukum dalam bentuk pasal-pasal pidana. Selanjutnya, dalam perjanjian lisensi, hanya mampu menuangkan klausul-klausul sebagai kehendak kedua belah pihak. Akan tetapi 327 M. Solly Lubis, Sistem Nasional, Mandar Maju, Bandung, 2002. Satjipto Rahardjo, Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1977. Lihat juga Satjipto Rahardjo, Hukum Progrresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Genta Publishing, Jakarta, 2009. 329 Cara pandang linier itu adalah cara pandang yang mengacu pada satu garis lurus atau dengan kata lain cara pandang “kacamata kuda”. Satu contoh yang sederhana adalah ketika seorang petani menanam pisang. Pertanyaan yang diajukan adalah untuk apa ia menanam pisang, jawabnya adalah “untuk dimakan”. Pertanyaan berikutnya adalah untuk apa makan ? Jawabnya adalah “untuk menambah tenaga”. Pertanyaan selanjutnya : untuk apa tenaga ? Jawabnya adalah : “untuk bisa mengayunkan cangkul”. Pertanyaan berikutnya adalah : untuk apa mencangkol ? Jawabnya : “untuk menanam pisang”. Petani ini dalam menjawab tiap-tiap pertanyaan menggunakan cara pandang linier. Padahal tenaga itu tak mesti digunakan untuk mencangkol tanah dan untuk menanam pisang. Boleh juga tenaga itu digunakan untuk pekerjaan yang lain misalnya mendirikan bangunan, boleh juga yang ditanam itu tidak hanya pisang, tetapi juga kelapa sawit yang tidak serta merta buahnya dapat dimakan. Jika petani ini menggunakan cara pandang terakhir, itu berarti petani tersebut telah menggunakan cara pandang non linier. Begitulah hukum dalam proses penegakannya tidak tunduk pada cara pandang yang linier tapi tunduk pada cara pandang non linier. Ada banyak faktor non hukum yang bekerja dalam proses penegakan hukum. Lebih lanjut lihat Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 3. 328 400 hukum tidak menjamin bahwa potret empiriknya akan sama seperti yang dituangkan dalam undang-undang atau perjanjian itu. Sebagai contoh : Pasal 72 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2002 merumuskan : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Akan tetapi sampai hari ini belum ada pelaku tindak pidana pembajakan hak cipta yang dihukum seperti ketentuan Pasal 72 ayat (1) tersebut. bahkan sampai hari ini belum ada perkara pidana pelaku pembajakan hak cipta karya sinematografi yang diproses di Pengadilan padahal dalam kenyataannya, pelanggaran atau pembajakan karya sinematografi terus berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Jika menggunakan sudut pandang linier maka seharusnya para pelaku pembajakan hak cipta karya sinematografi sudah harus dihukum. Industri illegal VCD dan DVD bajakan yang mengisi 80 % pasar di Indonesia seharusnya sudah dapat ditutup bila di lapangan dilakukan penyitaan sesuai amanah Undang-undang No. 19 Tahun 2002. Gambaran yang diungkapkan terakhir ini hanya dapat terjadi jika menggunakan cara berpikir linier, seperti ilmu fisika dan matematika. Akan tetapi cara melihat hukum tidak dapat menggunakan optik seperti itu. Hukum mempunyai 3 cara pandang. Pertama cara pandang filosofis, kedua adalah cara pandang sosoliogis dan ketiga cara pandang empiris. Karena itu hukum tidak bisa dilihat hanya menggunakan optic linier tetapi harus menggunakan optic non linier. Sudah terlalu lama negeri ini menempatkan hukum melalui satu sudut pandang yakni sudut pandang normatif. 330 Sarjana Hukum yang lahir kemudian adalah Sarjana Hukum “tukang” bukan Sarjana Hukum yang arsitek. Akibat lebih lanjut adalah dalam praktek 330 Di berbagai Fakultas Hukum di Indonesia, muatan kurikulum pendidikan bidang ilmu hukum masih didominasi oleh studi hukum normatif. Kajian-kajian sosiologi hukum, politik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum dan bahkan filsafat hukum hanya diajarkan untuk melengkapi kajian studi hukum normatif. Tidak ada program studi ilmu hukum yang secara khusus ditetapkan yang mengacu pada studi hukum empirik, misalnya program studi hukum dan masyarakat atau program studi politk hukum. Pengembangan studi ilmu hukum empirik saat ini yang dikembangkan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara sendiri sampai hari ini belum mengembangkan pemikiran ke arah itu. 401 penegakan hukum para sarjana hukum terlihat kaku dan berujung pada kesan tidak profesional. Keluwasan dalam memandang obyek hukum dalam perspektif non linier dapat dilihat dari matrik di bawah ini. Matrik 37 Paradigma Hukum Paradigma Konsep Filosofis ideologi Juridis/ normatif Sosiologis/ empiris Hukum Sebagai Asas Moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal Hukum sebagai kai dah/norma sebagai produk eksplisit dari sumber kekuasaan politik yang sah. Hukum sebagai institusi sosial yang ril dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat Tujuan Bidang Kajian Hukum Keadilan Filsafat Hukum Kepastian Hukum Jurisprudence (ilmu hukum normatif Kemanfaatan Sosiologi Hukum Antropoligi Hukum Sejarah Hukum Psikologi hukum Law and Society Law in Action Ajaran tentang hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, 331 a. b. memiliki multiparadigm Paradigma filosofis - ideologis, yakni memandang hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal, dan menjadi bagian inheren dari sistem hukum alam, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan ; Paradigma juridis - normatif yakni : hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu, dan terbit sebagai 331 Gustav Radbruch, Rechts-Philosophie, K.F. Koehler Verlag Stuttgart, Germany, 1956. Lihat lebih lanjut F.S.C. Northrop, Cultural Values, dalam Sol Tax, ed., Antropological Today : Selections (Chicago, Chicago University Press, 1962), hal. 422435, Herbert L.A. Hart, The Concept of Law (London : Oxford University Press, 1972) : dan Leon H. Mayhew, The Legal System serta Paul Bohannan, Law and Legal Institutions, kedua-duanya dalam David L. Sills, ed. International Encyclopedia of the Social Sciences (New York : Mac Millan, 1972), Jilid IX, hal. 59-66 dan 73-78. Northrop sebenarnya menyebutkan 5 konsep, namun dua konsep yang diberikan olehnya (yaitu konsep Legal Realism dan konsep Kesenian) khusus untuk pembicaraan kali ini bukunya hanya mengulas konsep (a) dan (b) saja, sedangkan Mayhew dan Bohannan memaksudkan hukum semata-mata dalam konsep tersebut (c). 402 c. produk eksplisit suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi ; yang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum ; Paradigma sosiologis - empiris yakni : hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam sistem kehidupan bermasyarakat, baik dalam prosesproses pemulihan ketertiban dan penyelesaian sengketa maupun dalam prosesproses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru, yang bertujuan untuk memberi kemanfaatan bagi masyarakat. Konsep tersebut pada butir (a) di atas adalah konsep yang berwarna moral dan filosofis, yang melahirkan cabang kajian hukum yang amat moralistis dengan bidang kajiannya Filsafat Hukum. Konsep tersebut pada butir (b) merupakan konsep positivistis - tidak hanya yang Austinian melainkan juga yang pragmatik-realis dan yang NeoKantian atau Kelsenian - yang melahirkan kajian-kajian ilmu hukum positif atau dalam terminologi Inggeris disebut "jurisprudence". Dan akhirnya, konsep-konsep tersebut pada butir (c) adalah konsep sosiologi atau antropologik, yang kemudian melahirkan kajian-kajian sosiologi hukum, antropologi hukum, atau juga cabang kajian yang akhir-akhir ini banyak dikenal dengan nama "Hukum dan Masyarakat", atau Law in Society, Law in action. 332 Harus disadari bahwa ketika Amerika dan negara-negara industri maju “memaksa” Indonesia untuk turut serta dalam kesepakatan GATT 1994/WTO dan konsekuensinya, Indonesia harus tunduk pada kesepakatan itu. Khusus dalam lapangan hak kekayaan intelektual karena dimasukkannya issu hak kekayaan intelektual dalam kesepakatan tersebut mengharuskan Indonesia menyesuaikan peraturan perundang-undangan HKI-nya dengan TRIPs Agreement. Langkah yang dilakukan oleh Amerika dan negara-negara maju adalah langkah 332 Melihat hukum dengan cara pandang seperti pada bagan di atas akan menggiring pikiran kepada sesuatu yang mendekati kebenaran. Sebaliknya jika menggunakan cara pandang linier satu sudut pandang saja, sudut pandang kacamata kuda, hal ini semakin menjauhkan obyek yang dipandang dari kebenaran. Lihatlah bagaimana prediksi para ekonom di tahun 1970-an yang tak pernah memperhitungkan Cina, India dan Turki akan sukses ke depan pasca krisis moneter tahun 1988. Hari ini negara yang tak pernah diprediksi memperoleh pertumbuhan ekonomi yang baik pasca krisis moneter itu ternyata akan tampil sebagai raksasa ekonomi dunia, walaupun ini prediksi para ekonom yang terbaru lagi dengan cara pandang juga. Ilmu ekonomi pun gagal menggunakan sudut pandang linier Lihat lebih lanjut John & Doris Naisbitt, China’s Megatrends 8 Pilar Masyarakat Baru, (Terjemahan Hendro Prasetyo), Gramedia, Jakarta, 2010. Lihat juga Gregory C. Chow, Interpreting China’s Economy, Terjemahan Rahmani Astuti, Memahami Dahsyatnya Ekonomi China, Metagraf, Solo, 2011. Lihat juga PT. Kompas Media Utama, India Bangkitnya Raksasa Baru Asia Calon Pemain Utama Dunia di Era Globalisasi, Kompas, Jakarta, 2007. Lihat juga Kishore Mahbubani, Asia Hemisfer Baru Dunia Pergeseran Kekuatan Global ke Timur yang Tak Terelakkan, Kompas, Jakarta, 2011. 403 politik (politik ekonomi dan politik hukum). Bagi Indonesia, TRIPs Agreement mempengaruhi program legislasi nasionalnya dan itu berdampak pada pilihan politik hukum. Sekali lagi, ternyata kajian hukum bukan kajian “hitam-putih” tapi dipengaruhi oleh “warna-warna lain”. Sebagai akibat dari pilihan politik hukum semacam itu, maka penegakan hukum dalam lapangan hak kekayaan intelektual khususnya dalam hal perlindungan karya sinematografi menjadi terpengaruh juga. Hal ini juga membawa dampak kepada kesiapan aparat penegak hukum dalam praktek penegakan hukumnya. Dalam kesepakatan GATT 1994/WTO, sesungguhnya telah mengecilkan sudut pandang legalistik yang dianut selama ini dengan besarnya peranan negosiasi yang dibuka oleh sistem GATT. Terdapat 19 klausul dalam perjanjian GATT yang mewajibkan para pihak untuk bernegosiasi. Keberhasilan negosiasi bersumber dari hubungan pribadi yang terbentuk diantara para delegasi dalam setiap perundingan untuk menyelesaikan sengketa. Jika langkah ini yang harus ditempuh, maka yang mengemuka adalah bukan sudut pandang legalistik tetapi sudut pandang politik. Kepiawaian para perunding menjadi kunci utama dalam penyelesaian sengketa. Demikian juga yang termaktub dalam Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 tentang Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa seperti yang diatur dalam Pasal 65. 333 Penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution) tentu saja keluar dari perspektif hukum normatif atau legalistik tetapi lebih mengarah pada paradigma sosiologis-empirik. Oleh karena itu jika penegakan hukum untuk melindungi pembajakan karya sinematografi semata-mata diharapkan dari penegakan hukum pidana yang mengandalkan penyidik dalam hal ini pihak Kepolisian Republik Indonesia, maka dikhawatirkan upaya untuk menuntaskan praktek pembajakan atau pelanggaran hak cipta sulit untuk diakhiri. Karena itu harus ada solusi-solusi alternatif yang dapat dilakukan melalui pendekatan integratif hukum yang multiparadigma itu. Sebab bagimana pun juga kultur birokrasi yang korup itu, tetap akan memberikan pengaruh dalam proses penegakan hukum. Lembaga penegak hukum beserta aparatnya, sebenarnya lebih menyukai jika dalam kasus itu melibatkan kalangan birokrasi, sebab di sampaing 333 Tentang tatacara penyelesaian sengketa di luar pengadilan lebih lanjut lihat Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2002. 404 perkara yang ditangani itu memiliki prestise, juga berpeluang untuk terjadi transaksional. Prilaku budaya kalangan birokrasi baik secara kelembagaan maupun secara individu dalam peneyelesaian kasus hukum yang menimpa mereka melalui proses “mafia hukum” telah banyak “menyumbangkan” kultur atau budaya negatif bagi proses pembangunan peradaban bangsa yang taat hukum. Masyarakatpun akhirnya apatis dengan situasi semacam itu. Belum lagi para koruptor yang mengakhiri masa pemidanaannya disambut dengan gegap gempita oleh para pendukung dan simpatisannya. Padahal di negara-negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum, pada tataran pelanggaran moral sajapun kalangan birokrat itu sudah “diharuskan” dengan sukarela untuk menundurkan diri dari jabatan publik. Justeru di Indonesia menjadi terbalik, mereka yang sudah pernah dihukum, malah bersikukuh untuk dicalonkan menjadi pejabat publik. Sebuah perkembangan peradaban budaya hukum yang ironis, yang tak dapat dijelaskan dengan menggunakan teori Talcott Parson, Emile Durkheim atau Max Weber dan mungkin hanya dapat dijelaskan dengan Teori Physico Analis-nya Sigman Frud. Kalangan birokrat yang menduduki jabatan publik yang melakukan pelanggaran moral dan hukum di negeri ini, tercatat mmulai dari tingkat Presiden sampai ke tingkat pemerintahan Kabupaten/Kota. Matrik di bawah ini memperlihatkan gambaran yang nyata tentang itu. Matrik 38 Pejabat Eksekutif Terlibat Kasus Pelanggaran Hukum dan Etika No 1. Jabatan Dalam Pemerintah Presiden Nama Soekarno Soeharto B.J. Habibie K.H.Abdul Rahman Wahid Megawati Soekarnoputri Susilo Bambang Yudhoyono Kasus Hukum/Etika yang Dilanggar Penyimpangan konsep demokrasi Pancasila yang diatur dalam UUD ’45 dengan melahirkan TAP MPRS yang menetapkannya sebagai Presiden Seumur Hidup. Dipersangkakan melakukan berbagai tindakan yang bersifat kolusi, korupsi dan nepotisme. Pertanggung Jawaban akhir jabatan sebagai presiden ditolak MPR Keterlibatan dalam kasus Buloq Gate dan Brunei Gate Tidak memperlihatkan sikap sebagai negarawan yang mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan untuk pembangunan nasional. Pelanggaran etik dan moral 405 2. 3. 4. 5. Menteri Pemuda Olahraga Menteri Pertanian Menteri Keuangan Andi Malarangeng & Siswono Kasus Import Daging Sapi Sri Mulyani Bill Out Century, disidangkan sebagai saksi, tapi dianggap sebagai orang yang mengetahui. Kasus Korupsi PON, dalam tahap penyidikan Kasus Dana Bantuan Sosial Korupsi di BI Cek Pelawat Gratifikasi Bill Out Century, tahap penyidikan Korupsi, tahap penyidikan Menko Kesra Agung Laksono Menteri Sosial Gubernur BI Bachtiar Chamsjah Syahril Sabirin Miranda Gultom Boediono Gubernur Kepala Daerah 1. Fadil Muhammad (Gorontalo) Sulbar 2. Syamsul Arifin (Sumut) 3. Rusli Zainal, Gubernur Riau 4. Gatot Pujo Nugroho 1.Abdillah, Walikota Medan 2.Rahudman, Walikota Medan 3.Risuddin, Asahan 4.RE. Siahaan, Siantar 5.Hidayat Batubara, Bupati Madina 6. Rahmat Yasin, Bupati Bogor 7. Agus Paturachman, Bupati Sragen 8. Rina Iriani, Bupati Karanganyar 9.Bupati Kutai 10.Bupati Pelalawan 11. Bupati Banyuwangi 12. Djoko Nugroho, Bupati Blora 13. Achmat Dimiyati Natakusumo, Bupati Barito Utara 14. Bupati Banyuwangi 15. Binahati Benedictus Baeha, Bupati Nias 16. Fonaha Zega, Bupati Nias Utara Bupati/ Walikota Kepala Daerah kepemimpinan Mencampur adukkan tugas politik dengan tugas kenegaraan. Kasus Suap Hambalang, dalam tahap penyidikan Korupsi, telah diputus Korupsi, tersangka di KPK Korupsi, tersangka di KPK Korupsi, sudah diputus Korupsi sedang dalamproses penuntutan Korupsi, sudah diputus Korupsi, proses penyidikan Korupsi, proses penuntutan Korupsi, telah diputus Korupsi Korupsi Korupsi Korupsi Korupsi Korupsi Korupsi Korupsi Korupsi Korupsi Sumber : Diolah dari berbagai sumber Meskipun dalam sejarah kepemimpinannya terdapat banyak kritikan terutama dari aspek pelanggaran hukum dan etika, akan tetapi harus diakui mereka juga memberikan sumbangsih yang sangat berarti bagi negeri ini melalui capaian-capaian pada periode kepemimpinannya. Presiden Soekarno, misalnya berhasil mempersatukan Indonesia dan meletakkan sendi ideologi Pancasila. Presiden Soeharto berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membumikan Pancasila melalui P4. Selanjutnya Presiden B.J. Habibie berhasil membuka kran 406 demokrasi. Presiden K.H. Abdul Rahman Wahid, berhasil menghapuskan diskriminasi etnik. Kemudian Megawati Soekarnoputri berhasil meletakkan dasar pembangunan ekonomi dengan menciptakan iklim yang kondusif walaupun kondisi itu tidak dapat bertahan sampai di masa akhir jabatannya sedangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berhasil menegakkan sendi-sendi demokrasi, transparansi, good governance. Dalam banyak hal kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh esksekutif lebih dari sekedar persoalan rendahnya tingkat penghasilan mereka sebagai pejabat publik, akan tetapi telah menjadi lingkaran tak berujung yang telah membudaya di kalangan birokrasi. Kekuasaan, demikian kata Lord Acton, cenderung untuk korup. Kekuasaan eksekutif di Indonesia jika ditelusuri dalam tabel di atas hampir dapat dipastikan terjerat dalam dalam lingkaran budaya korup. Namun demikian sulit juga untuk mengawali satu kesimpulan bahwa korup di kalangan birokrasi telah membudaya, sebab dalam banyak hal sistem pemerintahan dan bentuk negara yang membuka peluang para pejabat birokrasi tak terhindar dari praktek korupsi. Dalam sebuah wawancara dengan mantan pejabat daerah 334 yang pernah terjerat kasus korupsi, beliau mengatakan : Yang membuat orang jadi korup itu karena sistem yang ada yang membuka atau mempersilahkan orang untuk menjadi korup. Saat dilakukan penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan saya juga mengatakan saya tidak bersalah. Akan tetapi karena tindakan yang saya ambil itu merugikan keuangan negara dan memperkaya orang lain, saya harus dijatuhi hukuman. Padahal dalam kasus itu saya hanya menjalankan perintah Mendagri sebagai atasan saya melalui telegramnya. Seharusnya saya tak dapat dipersalahkan, karena atas perintah atasan. Hanya saja sebenarnya pada waktu itu saya dapat saja menolak permintaan mendagri itu, akan tetapi etika dan moral kepemimpin yang terbangun selama ini sulit untuk saya elakkan. Faktor kultur itu sangat kuat. Ada semacam budaya yang sudah terbentuk dari leluhur yang sulit untuk disimpangi sebagai ikatan moral tak tertulis, sebagai kultur birokrasi yang mengikat para pejabat di daerah, ketika permintaan itu datang dari Pusat. Di sinilah awal terbangunnya budaya birokrasi yang cenderung menyimpang dari tuntutan profesionalisme. Jadi untuk kasus saya sistemlah yang menggiring saya untuk masuk ke alam birokrasi yang korup. Sebuah ungkapan yang menarik, tidak semua para koruptor versi pengadilan itu adalah benar-benar korup, tetapi sistem pemerintahan dan bentuk negara dan budaya birokrasi yang terbangun selama ini yang menggiringnya menjadi koruptor. Lebih lanjut dalam wawancara yang sama, A menegaskan ; 334 Wawancara dengan A, di Medan, tanggal 11 Agustus 2012, pukul 20.14. 407 Jika hendak ditelusuri, semua pejabat di Republik ini tidak ada yang bersih dari prilaku korupsi. Mereka yang dulu pernah diadili atau sekarang sedang diadili, adalah mereka-mereka yang sial atau lagi apes saja. Jika diperiksa semuanya akan terkena jeratan hukum, sebab bukan orang atau pejabatnya yang korup, tapi sistemnya. Ketika orang masuk ke dalam sistem itu, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka dia akan terbawa oleh arus sistem itu menjadi korup. Seumpama jalan sudah berlumpur, siapapun akan melintasi jalan itu pasti akan terkena percikan lumpur. Akan tetapi ada orang yang lebih cerdik, ketika ia sampai keseberang jalan, ia langsung membersihkannya, sehingga percikan lumpur tak kelihatan lagi. Celakanya di seberang jalan sudah ada menunggu “tim pengintai” yang siap memotret setiap orang yang melintas di jalan itu dan diantara tim pengintai itupun sudah siap berbagi air untuk membersihkan percikan-percikan lumpur. Khusus mengenai lembaga KPK, lebih lanjut beliau mengatakan : KPK lembaga yang kecil tapi memiliki kewenangan besar. Kenapa orang lebih profesional, karena kebutuhan, fasilitas untuk melaksanakan tugasnya terpenuhi dan kewenangan yang diberikan kepada KPK secara penuh dan tak ada pada lembaga penegak hukum yang lain. Biaya untuk menangani perkara telah tersedia anggran yang cukup, sedangkan pada lembaga penegak hukum yang lain, untuk beli kertas saja dananya tak cukup tersedia. Menarik perumpamaan yang dikemukakan oleh A di atas. Tak ada pejabat eksekutif yang dapat mengelakkan dari jalan yang berlumpur itu, sebab sistem yang terbangun sudah seperti itu. Ketika dipertanyakan, apakah hal semacam itu tidak dapat dielakkan ? A memberikan keterangan lagi : Tidak mungkin dapat dielakkan. Karena sistem “upeti” sudah mendarah daging. Hampir semua pejabat di Pusat menunggu “setoran” Tidak itu saja, mulai dari kalangan Partai Politik, aparat penegak hukum, wartawan, sampai pada LSM baik yang meminta dengan resmi maupun yang tidak meminta menjadi sebuah keharusan dan kebiasaan tidak tertulis harus “dialokasikan dana khusus” walaupun pemberiannya dilakukan secara santun, padahal dalam anggaran resmi dana-dana semacam itu tidak ada dialokasikan. Iklim birokrasi dan sistemlah yang menciptakan birokrasi yang menggiring kalangan eksekutif dan mungkin juga kalangan legislatif dan judikatif terjebak pada arus gelombang korupsi. Jika demikian halnya, agaknya restorasi terhadap bentuk negara dan sistem pemerintahan perlu segera dilakukan dan mendapat perhatian khusus dari kalangan politisi, tehnokrat dan negarawan serta kaum intelektual di negeri ini. Di bawah rezim negara kesatuan praktek-praktek pelanggaran hukum, korupsi dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Negara Kesatuan telah banyak menciptakan budaya birokrasi yang korup dengan mata rantai yang sangat panjang. Ketika pada tingkat pemerintahan daerah dan aparat penegak hukum daerah kasus itu muncul ke permukaan, tapi kemudian “ditutup” karena 408 adanya “permintaan” Pusat atau aparat penegak hukum yang secara kelembagaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi yang berkedudukan di Pusat. Adalah tawaran atau wacana bentuk negara federal menjadi perhatian khusus dalam studi ini, setelah melakukan analisis dengan menggunakan pisau politik hukum terhadap pilihan politik pragmatis dalam kasus transplantasi hukum asing ke dalam undang-undang hak cipta nasional. Karena pilihan politik transplantasi hukum tidak cukup hanya memusatkan aktivitasnya pada segi substansi hukumnya saja, akan tetapi juga pada struktur dan kulturnya. Faktor struktur dan kultur (budaya hukum) sangat dominan dalam penegakan hukum, tak cukup hanya normanya saja yang ditransplantasi, tapi juga struktur dan kulturnya. Karena itu menjadi relevan tulisan ini harus mengarak persoalan pada bentuk negara dan sistem pemerintahan yang dianut selama ini membuahkan struktur dan kultur yang membuka peluang bagi tumbuh suburnya praktek pelanggaran hukum, tidak terakomodirnya hak-hak rakyat serta semakin menipisnya rasa kebangsaan, tidak tersebarnya sumber daya ekonomi di setiap lapisan kehidupan masyarakat, timpangnya pembangunan antara Pusat dan daerah serta sederetan ketidak adilan yang melanda kehidupan bangsa yang melampaui setengah abad menjadi negara yang merdeka dan berdaulat adalah juga sebagai gelombang pemicu terciptanya sistem pemerintahan yang korup. Betapapan juga pengalaman prilaku budaya birokrasi selama ini telah menimbulkan banyak hambatan dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan. Praktek penegakan hukum yang selektif karena adanya intervensi eksekutif, menyebabkan penegakan hukum menjadi “pandang bulu” (menyimpang dari adagium, semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum) dan bersifat selektif dan praktek penegakan hukumnya menerapkan cara-cara “tebang pilih” bahkan kadang-kadang dapat “dipesan”. Asas praduga tak bersalah (presumption of innoncense) atau asas equality before the law tidak selalu dapat diterapkan dalam praktek penegakan hukum. Hukum menjadi alat kekuasaan, alat untuk melanggengkannya atau untuk sekedar melengserkan kekuasaan orang lain. Bak kata pepatah melayu, penegakan hukum yang selektif itu seumpama, tepat di mata dipicingkan (dipejamkan) tepat diperut dikempiskan. Hukum yang dapat menjerat penguasa atau koleganya, atau keluarganya menjadi “tumpul” dan tidak berfungsi. Penegakan hukumnya menjadi berhenti di tengah jalan. Inilah ironi kekuasaan eksekutif yang dalam banyak hal 409 “bersekutu” dengan “judikatif” dan menyimpang dari tradisi negara hukum menurut pandangan Dicey. 3. Budaya Hukum Judikatif Polisi yang selama ini dianggap sebagai garda terdepan yang secara struktural dikukuhkan sebagai lembaga resmi negara untuk melakukan penyidikan, ketika pelanggaran atau kejahatan terhadap karya sinematografi yang ditempatkan sebagai delik biasa, ternyata secara kelembagaan mereka diperlakukan “belum adil dan diskrimatif” dalam praktek sisitem pembinaan karir. Artinya di dalam tubuh institusi ini masih terdapat banyak persoalan-persoalan internal yang belum terselesaiakan. Terdapat 30 % dari total anggota Kepolisian Republik Indonesia yang puas atas langkah pembinaan karir personil kepolisian yang meliputi aspek : 1. Peluang untuk mendapatkan pendidikan termasuk penugasan dan pelatihan khusus di dalam dan luar negeri dalam rangka pengembangan karir. 2. Kebijakan mutasi dan promosi termasuk penempatan 3. Punishment dan reward. 335 Hasil penelitian ini menjadi peringatan bagi institusi Polri. Angka 30 % yang menunjukkan kegagalan dalam penerapan kebijakan pembinaan institusi Polri merupakan angka yang sangat kritis dan ini berpengaruh pada sikap dan budaya penegakan hukum aparat penegak hukum. Keadaan ini tidak hanya menyangkut personil kepolisian saja tetapi juga sudah merambah ke institusi-institusi penegak hukum lainnya, baik itu menyangkut moralitas maupun menyangkut profesionalisme. Moralitas dan profesional aparat penegak hukum berada pada titik nadir. Mulai dari kasus Antasari (Ketua KPK terlibat kasus 335 Alantin S., Persepsi Anggota Polri Terhadap Sistem Pembinaan Karier Personil Polri, Makalah, disampaikan pada Seminar yang dilaksanakan di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, 1 Agustus 2013. Seminar ini didahului dari lapora n penelitian yang dilakukan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) dengan memilih responden secara acak yang ditetapkan sebanyak 1.000 orang dengan metode multistage sampling yakni didahului dengan menetapkan lokasi penelitian di 4 kepolisian daerah ya ng mewakili tiap-tiap kepulauan yang besar. Untuk Pulau Sumatera diwakili oleh Polda Riau, untuk Pulau Jawa diwakili oleh Polda Jawa Timur, untuk Sulawesi diwakili oleh Polda Sulawesi Utara, untuk Kalimantan diwakili oleh Polda Kalimantan Timur. Penelitian ini didasarkan pada landasan teori persepsi, faktor dalam pembinaan karier personil Polri, manfaat sistem karier terhadap organisasi Polri. 410 pembunuhan), Susno Duadji (Polisi terlibat kasus Korupsi), Joko Soesilo (Polisi terlibat Kasus Simulator SIM), Cyrus Sinaga (jaksa terlibat melindungi Koruptor Pajak Gayus Tambunan), Setyabudi Tedjocahyono (hakim terlibat Korupsi, sampai pada Akil Muchtar (tertangkap tangan kasus suap), Ketua Mahkamah Konstitusi yang secara hirarkhis menempati posisi lembaga peradilan tertinggi yang putusannya tak dapat diadili lagi oleh lembaga peradilan lain di Indonesia. Matrik berikut ini mencoba untuk menyederhanakan berbagai keterlibatan aparat penegak hukum dalam berbagai bentuk pelanggaran hukum mulai dari tingkat penyidikan (kepolisian, jaksa, KPK) , penuntutan (jaksa, KPK) sampai pada tingkat pemeriksaan dan Keputusan (Hakim PN, PT, Tipikor, TUN, MK dan MA). Matrik 39 Pelanggaran Hukum Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum. No 1. Jabatan/Unit Kerja Kepolisian Nama Inisial Aparatur Kasus yang Dilanggar 1. SD Suap untuk memuluskan kasus PT. Salmah Arowana Lestari (SAL) dan pemotongan dana pengamanan Pilgub Jawa Barat Korupsi Simulator SIM Suap dalam kasus BLBI Suap dalam kasus penggelapan pajak tersangka Gayus Tambunan Pembunuhan Tuduhan kriminal Tuduhan kriminal Tuduhan kriminal Pelanggaran Etik Menerima Suap Untuk Memuluskan Perkara Menerima Suap Untuk Memuluskan Perkara Menerima Suap Untuk Memuluskan Perkara 2. DS 2. Kejaksaan Agung 1. UTG 2. CS 3. Komisi Pemberantasa n Korupsi (KPK) 4. Hakim Pengadilan Tipikor 1. AA 2. BSR 3. CH 4. NB 4. AS 1. KM 2. HK 5. Hakim Pengadilan Niaga Hakim adhoc pengadilan industrial Hakim Pengadilan Tinggi TUN 6. 7. SU IDS Menerima Suap Memuluskan Perkara Untuk 1. I Menerima Suap Memuluskan Perkara Untuk 411 8. 9. 10 11. 12. Pengadilan Pajak Hakim Mahkamah Agung Hakim Mahkamah Konstitusi Ketua Mahkamah Konstitusi Pengacara/ Advocat 2. TIP 3. AF 4. DG 5. SY 6. MYBG Suap tersebut berkaitan dengan pengajuan kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait terbitnya surat perintah penyelidikan (Sprinlidik) tentang dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dana bantuan sosial (bansos), bantuan daerah bawahan (BDB), bantuan operasional sekolah (BOS), dan penahanan pencairan dana bagi hasil (DBH) yang dilakukan Gubernur Sumatera Utara di PTUN, Medan. R dan AG Tertangkap tangan menerima suap DS Menerima Suap Memuluskan Perkara AS Pemalsuan surat MK AM Penyuapan dalam kasus Pilkada Lebak, Banten dan Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalteng Penyuapan terhadap mantan Kabag Reskrim Susno Duadji Praktek Penyuapan Perkara di MA - HH - L Untuk - OCK Penyuapan terhadap pengajuan kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait terbitnya surat perintah penyelidikan (Sprinlidik) tentang dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dana bantuan sosial (bansos), bantuan daerah bawahan (BDB), bantuan operasional sekolah (BOS), dan penahanan pencairan dana bagi hasil (DBH) yang dilakukan Gubernur Sumatera Sumber : Diolah dari berbagai sumber 412 Matrik di atas adalah gambaran kecil saja dari berbagai pelanggaran besar yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di negeri ini, baik yang terungkap di publik maupun yang tidak terungkap. Aparat penegak hukum yang diharapkan sebagai ujung tombak untuk memberikan perlindungan kepada publik, justeru mereka yang mencederainya. Aparat penegak hukum yang diharapkan sebagai wakil Tuhan di muka bumi unutk menciptakan keadilan, justeru mereka yang memporak porandakan dan mengoyak-ngoyak rasa keadilan. Peristiwa ini dapat diungkapkan dalam satu adagium singkat yang menggambarkan tentang perilaku aparat penegak hukum Indonesia hari ini yakni, ”bak pagar makan tanaman”. Kalau hewan ternak makan tanaman, masih ada yang dapat dilakukan, paling tidak hewan ternak itu masih bisa dinikmati dagingnya. Kalau aparat penegak hukum yang “mencurangi” hukum, keadaan ini akan mempercepat kehancuran negeri ini. Pertarungan internal Indonesia ke depan bukan lagi berkutat pada persoalan perebutan kekuasaan, atau persoalan pendidikan dan kesehatan atau masalah sandang pangan, akan tetapi akan bergerak pada persoalan penegakan hukum dan keadilan. Gambaran yang dilukiskan pada matrik di atas mengantarkan pada satu kesimpulan bahwa , profesionalisme aparat penegak hukum tak dapat diharapkan lagi . Tak dapat lagi digantungkan harapan bangsa ini untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta melindungi segenap tumpah darah Indonesia kepada aparat penegak hukum. Bagaimana bisa menciptakan halaman dan lantai yang bersih, jika disapu dengan penyapu yang kotor? Uraian-uraian di atas adalah merupakan untaian cerita empirik sebagai potret nyata, bukan lukisan abstrak tentang kebobrokan penegakan hukum yang disebabkan oleh tidak profesionalnya aparat penegak hukum. Hilangnya rasa tanggung jawab moral dan tanggung jawab sosial aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas mulia yang diembannya. Tak ada lagi rasa bersalah, ketika mereka makan dan minum dari bumi Indonesia yang diberi tugas melindungi hak-hak anak bangsa tapi justeru tampil sebagai “piranha” yang memakan anak bangsanya sendiri. Menggerogoti sumber ekonomi negara yang seyogyanya untuk kepentingan hidup bersama, tapi justeru dinikmati sendiri. Tak ada lagi akal sehat, tak ada lagi hati nurani. Ini adalah gambaran makro penegakan hukum di negeri ini. Gambaran mikro tentang penegakan hukum dalam bidang hak cipta khususnya dalam bidang sinematografi, tidaklah jauh berbeda dengan gambaran makro tersebut. Aparat penegak hukumnya masih sama, polisi, jaksa dan hakim. Hanya KPK yang tidak terlibat, karena 413 tidak ada unsur korupsinya. Akan tetapi bila ditelusuri dan dicermati lebih lanjut efek penghancuran sendi-sendi kehidupan sosio-kultural karena ketidak profesionalan aparat penegakan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak cipta bidang karya sinematografi ini, tak beda jauh dengan efek penghancuran yang diakibatkan oleh perilaku korupsi. Jika kasus Bill Out Bank Century yang melibatkan pejabat tinggi negara dan Kasus Impor Daging Sapi yang melibatkan Menteri dan politisi partai yang dikenal “bersih dari korupsi dan pelanggaran moral” justeru dalam prakteknya merugikan keuangan negara dan dampaknya merugikan ekonomi negara. Merugikan ekonomi negara berarti mengurangi hak dan kenikmatan warga negara. Tidak jauh berbeda dengan kasus-kasus yang kelihatan merupakan “kasus besar” dalam kasus pelanggaran atau pembajakan hak cipta atas karya bidang sinematografipun sebenarnya merupakan “kasus besar”, di samping langsung merugikan keuangan negara karena hilangnya pajak penjualan yang mencapai triliunan rupiah, juga tindakan pembajakan itu telah membunuh kreativitas anak bangsa untuk berkarya. Dampaknya adalah terjadi kemunduran dalam industeri perfilman nasional, yang berujung pada hilang dan matinya kreativitas para pencipta di bidang penulisan novel atau skenario film. Masyarakat konsumen terbiasa menikmati karya hasil pelanggaran hukum dengan mengeluarkan biaya murah. Terbentuk budaya dan peradaban pragmatis dan budaya “lenggang kangkung atau easy going” tak peduli hak siapa yang dilanggar. Inilah pembelajaran “pola tingkat dasar korupsi”. Lama kelamaan menjadi budaya korupsi. Jika dari kecil teranjak-anjak, sudah dewasa terbawa-bawa, maka sesudah tua berubah tidak. Ini kata pepatah Melayu kuno. Perilaku buruk yang dibiarkan terus berjalan tanpa ada pencegahan, lambat laun akan diterima sebagai kebiasaan dan kata pepatah Arab, “merubah kebiasaan akan menimbulkan musuh. ” Sulit untuk merubah perilaku para pembajak karya cipta sinematografi dan merubah pola perilaku para konsumen, ketika pola perilaku aparat penegak hukum tidak berubah. Perubahan seperti apa yang diharapkan dari aparat penegak hukum ? Melakukan penyelidikan, penyidikan atau pemeriksaan terhadap tiap-tiap adanya indikasi pelanggaran hak cipta bidang karya sinematografi? Apakah pekerjaan ini menantang atau dapat menaikkan karir ? Apakah ini membuat anggota atau aparat penegak hukum menjadi terkenal dan populer seperti Briptu Norman? Tak ada yang menarik dari pekerjaan ini, kecuali menimbulkan banyak musuh. Tak ada popularitas, sekalipun dengan menangkapi seluruh pengedar karya cipta sinematografi bajakan. Tak 414 ada adrenalin yang terpacu dalam menangani para konsumen yang membeli karya sinematografi bajakan, dibanding dengan menangkapi para pengedar dan pemakai narkoba jenis sabu misalnya. Menggerebek rumah yang memproduksi sabu, jauh lebih populer dari pada menggerebek rumah yang di dalamnya memproduksi VCD atau DVD illegal. Reward and punishment lebih jelas dalam penangan kasuskasus semacam itu, daripada menangani kasus pembajakan kara sinematografi. Terjawab sudah, mengapa bidang penegakan hukum hak cipta untuk melindungi karya sinematografi ini tidak menarik perhatian aparat penegak hukum. Dalam sebuah wawancara dengan Pengurus Asosiasi Artis Sinetron Cabang Sumatera Utara 336 mengatakan : Tidak semua aparat penyidik Polri mengetahui tentang Undang-undang hak cipta. Saya pernah meangkap pelaku pembajakan. Pada waktu itu saya berpura-pura mau membuka usaha untuk pemutaran film sinema keluarga dan karauke. Saya minta untuk dikirim judul-judul film dan lagu-lagu. Kemudian mereka mengantarkan pesanan saya dan di antara pesanan itu ada karya sinematografi produksi kami. Saya langsung membawa pelakunya ke Poltabes Medan waktu itu. Kejadian itu sekitar 5 tahun yang lalu. Aparat kepolisian memproses pengaduan kami, tapi pelakunya tidak ditahan. Keesokan harinya saya datang untuk memanmtau perkembangan penyidikan. Ternyata penyidikan belum diproses karena aparat penyidik tak punya undang-undang hak cipta. Saya pergi ke toko buku untuk membeli buku undang-undang hak cipta dan menyerahkannya kepada penyidik. Beberapa hari kemudian saya pantau lagi perkembangannya, ternyata tak ada proses hukum. Saya kira perkara itu hilang lenyap begitu saja, tak sampai ke pengadilan, karena saya tak pernah dipanggil menjadi saksi. Wawancara di atas membuktikan bahwa aparat kepolisian tak pernah serius menangani perkara pembajakan hak cipta karya sinematografi. Di samping itu aparat kepolisian juga tidak semuanya memahami seluk beluk hukum pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam undang-undang hak cipta. Terlepas dari bekerjanya faktor non hukum, karena mungkin saja selepas pelaporan peistiwa itu mungkin saja pihak terlapor melakukan transaksional sebagaimana kelaziman dalam praktek penegakan hukum yang berlangsung selama ini. “Pernah juga selaku pengurus organisasi saya 337 mengajak Aparat Kepolisian untuk melakukan razia. Dalam razia itu sudah 336 Wawancara dengan Teruna Indra, Pengurus Asosiasi Artis Sinetron Cabang Sumatera Utara tanggal 21 Agustus 2013 jam 11.00 Wib, di Medan. 337 Wawancara dengan Pengurus Asosiasi Artis Sinetron Cabang Sumatera Utara tanggal 21 Agustus 2013 jam 11.00 Wib. 415 ditemukan titik terang bahwa penggandaan itu dilakukan oleh seorang Tionghoa di jalan Thamrin di Medan. Akan tetapi juga tidak ada tindak lanjut”, ungkap Teruna Indra. Semakin jelas bahwa penegakan hukum hak cipta akan sulit untuk dapat dilaksanakan dalam bebrapa tahun mendatang, jika tidak ada keinginan dan perhatian yang serius dari lembaga penegak hukum, khususnya lembaga kepolisian. Padahal menurut Pengurus Asosiasi Artis Sinetron Cabang Medan tersebut, begitu mudah untuk melacak pelaku pembajakan. Cukup diproses saja para penjual secara hukum, lalu kemudian ditanya dari mana mereka mendapatkannya. Dalam waktu 24 jam mata rantai pelaku tindak pidana pembajakan itu akan teruangkap. Seperti para pengedar atau bandar narkoba, cukup ditanya para pemakainya, kemudian akan diperoleh pengedarnya, untuk selanjutnya akan ditemuka siapa bandarnya. Akan tetapi hal semacam itu tidak pernah dilakukan secara serius oleh aparat kepolisian selaku penyidik dan diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membongkar jaringannya. Apalgi delik pelanggran hak cipta ini termasuk dalam katagori delik biasa, bukan delik aduan. Ada anggapan dari berbagai kalangan bahwa pelanggarann terhadap karya cipta bidang sinematografi belum menarik untuk diprioritaskan untuk ditegakkan. Menurut Pengurus Asosiasi Artis Sinetron Cabang Sumatera Utara : 338 Pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang harus menjadi titik berat profesi penegak hukum. Pekerjaan ini lebih sekedar pekerjaan fakultatif saja, pekerjaan tambahan jika masyarakat sudah resah. Sepanjang masyarakat “adem-adem” saja belum begitu mendesak untuk memberikan perlindungan hukum bagi sebagian dari “tumpah darah Indonesia” ini, apalagi dengan pembajakan karya cipta sinematografi ini, “tumpah darah Indonesia” yang lain banyak mendapat kenikmatan. Seumpama cerita “Robinhood” merampok (baca juga : korupsi) tapi hasilnya dibagi-bagikan kepada rakyat, dan ini dianggap biasa dan boleh. Hukum telah kehilangan “roh” –nya di bumi yang saling menghormati, saling menghargai hak orang lain. Ungkapan “tumpah darah” yang dimaksud oleh responden di atas adalah merujuk pada Pembukaan UUD 1945. Bahwa negara berkewajiban untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, akan tetapi mengapa ada perbedaan. Untuk kasus narkoba lebih diprioritaskan, sedangkan untuk kasus pelanggaran hak cipta cenderung 338 Wawancara dengan Pengurus Asosiasi Artis Sinetron Cabang Sumatera Utara tanggal 21 Agustus 2013 jam 11.00 Wib. 416 diabaikan. Padahal dampak yang ditimbulkannya juga sama, yaitu penghancuran peradaban. Pelanggaran terhadap hak cipta yang berlangsung selama ini, tidak hanya berpangkal pada ketidak tahuan aparat tentang arti penting perlindungan hak para pencipta, akan tetapi juga karena adanya “kesengajaan” para aparat untuk membiarkan pelanggaran itu terus berlangsung. Sebuah pembiaran struktural yang sangat sempurna. Ketidak pedulian aparat penegak hukum atas terjadinya pelanggaran hukum dalam bidang karya sinematografi, menyebabkan tidak ada satupun kasus pelanggaran hak cipta bidang karya sinematografi ini sampai ke Pengadilan. 339 Dalam sebuah wawancara dengan salah seorang aparat Kepolisian340 terungkap bahwa : Sebenarnya banyak anggota Polri yang mengetahui bahwa pembajakan hak cipta adalah merupakan perbuatan pidana. Akan tetapi kami selalu bekerja di bawah perintah atasan kami. Sekalipun delik pelanggaran terhadap hak cipta itu adalah delik biasa, artinya tidak perlu menunggu pihak yang dirugikan untuk membuat laporan pengaduan, kami bisa langsung melakukan tindakan penyidikan. Akan tetapi persoalan pelanggaran hukum di negeri ini sangat banyak. Dikumpulkan seluruh personil Kepolisian untuk melakukan penyidikan berbagai kasus pelanggaran hukum, jumlah personil itu tidak akan cukup. Apalagi untuk melakukan penyidikan diperlukan keahlian tertentu. Khusus untuk bidang Hak Cipta, tak semua juga personil kepolisian memahami seluk beluk undang-undangnya. Sementara di sisi lain kasus-kasus yang lebih prioritas untuk ditangani sudah menunggu, sehingga jarang sekali kami mendapat perintah dari atasan kami untuk melakukan penyidikan di bidang pelanggaran hak cipta. Berangkat dari wawancara di atas semakin jelaslah alasan mengapa kasus pelanggaran hak cipta bidang karya sinematografi tak pernah sampai ke Pengadilan. Teriakan para seniman tentang terjadinya pelanggaran atas hak cipta mereka adalah sebuah keluhan jiwa yang 339 Pembiaran ini sangat berbahaya secara kultural. Sebagai contoh ketika seekor kambing melahirkan, yang dapat dilihat adalah anak kambing yang lahir itu dilumuri oleh lendir. Jika lendir itu dibiarkan lengket ditubuh anak kambing itu dan induknya tidak segera mengambil inisiatif (boleh juga disebut instink) untuk membersihkannya, anak kambing itu dikhawatirkan tidak bisa berdiri dan hampir dapat dipastikan anak kambing itu akan mati. Manusiapun begitu juga. Jika seorang ibu hamil dibiarkan bersalin sendiri tanpa bantuan bidan, perawat atau dokter dikhawatirkan akan mengalami nasib yang sama dengan anak kambing. Bedanya induk kambing tak perlu bantuan paramedis atau “dukun melahirkan” atau tabib. Dokter hewanpun tak pernah dipanggil untuk persalinan seekor kambing. Apa yang ingin dijelaskan dari cerita itu ialah, itulah bahayanya sebuah “pembiaran” bagi kelangsungan alam dan makhluk hidup. Hewan dan manusia bisa punah, jika pembiaran terus berlangsung 340 Wawancara, tanggal 9 Oktober 2012, pukul 13.40 di Medan. 417 sia-sia. Pelanggaran terhadap hak cipta bidang karya sinematografi belum mendapat prioritas untuk ditangani, sekalipun kerugian yang diderita para seniman dan kerugian negara (akibat tidak masuknya pajak ke kas negara) mencapai ratusan milyar rupiah. Hal ini berkaitan dengan budaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Dalam sebuah sistem sosial yang “sakit” hampir dapat dipastikan seluruh komponen sub sistem terkontaminasi atau dalam bahasa ilmu kedokteran penyakit yang diderita sudah komplikasi. Ketika sub sistem legislatif terganggu, maka sub sistem eksekutif ikut juga terganggu dan pada gilirannya berpengaruh pula pada sub sistem lembaga dan aparat penegak hukum. Sulit untuk memisahkan rangkaian komponen dalam sub sistem yang saling berkait itu. Ketika penyidikan atas pelanggaran terhadap hak cipta tak pernah memasuki ranah hukum, maka tuntutan yang dilakukan oleh jaksa juga tak pernah ada, apalagi pemeriksaan pada tingkat Pengadilan. Dalam sebuah wawancara dengan pihak kejaksaan 341 terungkap bahwa ; Ada perbedaan kami dengan aparat kepolisian. Bahwa kami semuanya berlatar belakang pendidikan hukum. Sehingga seluk beluk pelanggaran hukum termasuk hak cipta sedikit banyak kami ketahui juga. Akan tetapi kami buklan penyidik untuk kasus pelanggaran hak cipta, karena itu tidak termasuk dalam tindak pidana khusus. Sehingga kami hanya bersifat pasif, menunggu dari hasil penyidikan pihak Kepolisian. Pihak kepolisian sulit juga untuk untuk dipersalahkan, karena ternyata untuk tiap kali melakukan penyidikan diperlukan biaya ekstra. Bahkan menurut pengakuan salah seorang penyidik 342dalam sebuah wawancara terungkap bahwa ; Untuk melakukan pemeriksaan kami harus mencari biaya sendiri. Abang pikir ada dana dari kantor kan? Tak ada sama sekali bang. Untuk kertas saja kami harus beli sendiri. Kadang-kadang penyidikan berlangsung hingga larut malam, untuk uang makan malampun harus biaya sendiri. Kalau untuk perkara yang ada uangnya, biasanya pihak yang diperiksa mau membiayai, tapi kalau perkara yang tak ada uangnya, itu hanya menjadi beban saja kepada kami. Jadi kadang-kadang ada perkara yang bisa diselesaikan secara damai, kami mendapatkan uang terlepas dari legal atau tidak legal. Uang itulah yang kami pergunakan. Tapi kalau kami harus memeriksa penjual CD dan DVD bajakan atau menangkap para pembelinya, itu namanya kurang kerjaan bang. Capek saja yang ada bang. Semakin jelas bahwa penegakan hukum hak cipta bidang karya sinematografi tak dapat disandarkan pada aspek pemidanaan, 341 Wawancara tanggal 6 Pebruari 2013, di Medan, pukul 16.15 Wawancara dengan PS, tanggal 9 Pebruari 2013 di Medan, pukul 17.15 342 418 sebab ujung tombak dari penyidikan yakni aparat kepolisian telah membuka “dapur” nya bahwa tak ada biaya ekstra untuk tiap-tiap penyidikan yang mereka lakukan. Sehingga mereka lebih memilih menyelesaikan delik aduan untuk kasus-kasus yang bernilai ekonomi. Sebab jika dapat diselesaikan dengan cara perdamaian mereka mendapatkan imbalan. Jadi semakin jauh dari harapan bahwa penegakan hukum hak cipta karya sinematografi akan sampai pada keinginan pencipta atau pemegang hak cipta. Alasan itu jugalah yang menyebabkan pelanggaran hukum terhadap hak cipta bidang karya sinematografi seolah-olah tidak tersentuh hukum atau lebih tepatnya terjadi semacam proses pembiaran. Apakah aparat kepolisian tidak mengetahui hal ini. Dari seluruh responden sebanyak 22 orang yang memberikan jawabannya melalui kuessioner 91,67 % mengetahui bahwa perbuatan mendagangkan atau membeli hasil VCD dan DVD bajakan adalah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, seperti terungkap dari tabel berikut ini. Tabel 1 Tingkat Pengetahuan Aparat kepolisian Terhadap Peristiwa Pidana Pembajakan Hak Cipta Karya Sinematografi. No 1. 2. Keterangan Mengetahui Tidak Mengetahui Total Sumber : Data Primer Frekwensi 22 2 24 Persentase 91,67 % 8,33 % 100 % Akan tetapi dari seluruh responden juga mengatakan, mereka tak pernah melakukan penyidikan, sekalipun mereka mengetahui peristiwa pidana pelanggaran hak cipta karya sinematografi itu adalah delik biasa, bukan delik aduan, seperti tertera pada tabel berikut ini. Tabel 2 Langkah Tindakan Yang Diambil Oleh Pihak Kepolisian Atas Pembajakan Hak Cipta Karya Sinematografi. No 1. 2. Keterangan Melakukan penyidikan Tidak melakukan penyidikan Total Sumber : Data Primer Frekwensi 24 0 Persentase 100 % 0% 24 100 % 419 Salah seorang jaksa 343 yang berhasil diwawancarai, justeru berkomentar lain lagi. Persoalan pelanggaran hak cipta, bidang karya sinematografi selama saya menjadi Kajari di 2 tempat tak pernah ada kasus yang sampai ke meja kami. Memang persoalan hak cipta ini persoalan hukum yang menarik, sekalipun masa saya kuliah dulu belum ada mata kuliah tentang hak cipta (maksudnya HKI, pen). Persoalannya mungkin persoalan besar, tapi itu bukan kasus yang menarik perhatian publik. Karena itu saya dapat memaklumi jika polisi tidak mengangkat kasus itu, karena tak ada pihak yang menyoroti kinerja mereka jika tak melakukan tindakan atas pelanggaran hak cipta itu. Berbeda jika perkara itu menyangkut pembunuhan atau kejahatan terhadap kehormatan yang bolak balik muncul di media atau adanya desakan LSM. Khusus untuk kasus pelanggaran hak cipta, media dan LSM pun tak tertarik untuk menyorotnya. Itu adalah salah satu faktor juga, mengapa persoalan ini tak pernah sampai ke ranah Pengadilan. Agaknya penjelasan T ini menjadi bahan kajian yang menarik, penegakan hukum oleh aparat penegak hukum baru benar-benar menjadi serius, jika banyak pihak yang “meribut”-kannya. Akan tetapi siap juga yang akan meributkannya untuk kasus pelanggaran hak cipta karya sinematografi ini ? Hampir semua anggota masyarakat, menjadi konsumen DVD dan VCD hasil produk illegal. Mungkin barangkali tidak hanya para wartawan atau anggota LSM para aparat penegak hukumpun menjadi konsumen DVD dan VCD illegal itu. Oleh karena itu begitu mudah untuk dipahami, mengapa aparat kepolisian sebagai ujung tombak penegakan hukum hak cipta tak mampu berbuat apapun atas tindakan pelanggaran hak cipta karya sinematografi. Jika diumpamakan aparat kepolisian seekor singa yang mengawasi gerak-gerik hewan-hewan yang melakukan kecurangan di wilayah kerajaan hutan, ketika seekor srigala memangsa, singa hanya duduk terdiam. Tak mampu berbuat apa-apa, karena sistem pengendalian keamanan di hutan itu sedang mengalami gangguan. Penelitian ini tidak menemukan perkara-perkara perdata dan perkara-perkara pidana dalam bidang karya cipta sinematografi yang sampai ke Pengadilan Negeri Medan dan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat juga. Tidak ditemukannya data tentang adanya kasus-kasus pelanggaran atau pembajakan karya sinematografi yang sampai ke ranah pengadilan, justeru menimbuklkan banyak prasangka. Ketika hukumnya ada (delik biasa), orang yang melakukan tindak pidana nyata-nyata ada (penjual dan pembeli karya sinematografi bajakan), aparat penegak hukum pun ada (aparat kepolisian), akan tetapi tidak ada satupun perkara pidana yang dilimpahkan ke pengadilan. Begitu 343 Wawancara, dengan T tanggal 19 Desember 2012, pukul 15.40 di Medan. 420 juga pihak pencipta dan produser yang dirugikan atas peristiwa pembajakan itu juga ada akan tetapi tidak pernah ada gugatan yang disampaikan ke Pengadilan Niaga. Sebuah fenomena hukum yang sangat menarik untuk dikaji secara akademis. Aparat penegak hukum terutama pihak kepolisian bukannnya tidak mengetahui pelanggaran hukum terhadap karya sinematografi itu telah terjadi dan terus berlangsung speanjang hari. Akan tetapi mereka “tak kuasa” untuk mencegahnya. Selain faktor anggaran juga faktor “struktural dan kultural” penegakan hukum dalam bidang ini sangat tidak mendukung. Proses pembiaran secara struktural atas pelanggaran hukum telah terjadi dan di mata aparat penegak hukum pembajakan hak cipta diposisikan sebagai perbuatan yang belum saatnya dikategorikan sebagai tindak pidana. Kesimpulan ini didasarkan pada wawancara dengan salah seorang aparat kepolisian : Selaku aparat kepolisian bukan kami tidak tahu bahwa perbuatan pembajakan hak cipta itu adalah suatu tindak pidana. Akan tetapi, kami juga memahami para penjual VCD dan DVD bajakan itu adalah pedagang kaki lima yang tergolong dalam kelompok ekonomi lemah. Para konsumen juga adalah ratarata mahasiswa dan anak-anak muda yang juga masuk dalam kategori orangorang yang sebenarnya tidak ingin memperkaya dirinya sendiri atau mendapat keuntungan yang besar dari tindakannya itu. Kalangan konsumen lain di luar mahasiswa dan anak-anak muda juga dari golongan masyarakat klas bawah, kalau mereka ada uang justeru mereka akan berbelanja di plaza di konter yang menjual VCD dan DVD original. Keuntungan penjual VCD dan DVD pun rata-rata Rp. 500,- s/d Rp. 1.000,- per keping, sehingga penghasilan mereka hanya cukup untuk makan sehari-hari. Terlalu berat juga bagi kami jika tindakan mereka ini harus dikategorikan sebagai sebuah kejahatan. Apalagi untuk menyidik perkara ini memerlukan waktu dan keahlian yang tidak semua aparat kami dapat melakukannya, ini belum lagi jika dihubungkan denagn anggaran biaya untuk melakukan penyidikan. Jika dibandingkan dengan prestasi yang akan diperoleh dari aktivitas penyidikan ini penanganan terhadap perkara ini tidak juga dianggap sebagai sebuah prestasi besar. Berbeda dengan penanganan terhadap perkara pidana yang lain seperti : tindak pidana narkoba atau kejahatan-kejahatan lain yang membahayakan keamanan dalam masyarakat. 344 Wawancara di atas, mengantarkan tulisan ini pada sebuah pertanyaan : Apakah sebuah kejahatan diukur dari faktor subyektifitas pelakunya ? Jika pelakunya adalah kalangan ekonomi lemah hukum menjadi tumpul ketika dihadapkan kepadanya. Sebuah tesis yang terbalik dari anggapan selama ini hukum akan tumpul ke atas akan tetapi menjadi tajam ke bawah atau dalam pepatah Melayu ”Jika jaring bocor, yang tertangkap adalah ikan besar dan ikan-ikan kecil akan 344 Wawancara dengan A pada tanggal 18 Juli 2012, pukul 11.00 Wib di Polresta Medan. 421 lolos, sebaliknya jika hukum ”bocor” maka yang tertangkap adalah orang-orang kecil dan orang-orang besar akan lolos”. Persoalan yang pelik saat ini yang dihadapi oleh para pemegang hak karya sinematografi adalah menghadapi pembajakan yang menggunakan teknologi cakram optik dan didukung oleh kemajuan teknologi informasi yang dapat mendownload karya sinematografi melalui jaringan internet. Itulah sebabnya kemudian Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 memasukkan satu norma tentang perlindungan hukum terhadap perbanyakan karya sinematografi melalui teknologi yang memanfaatkan kecanggihan informasi dan teknologi cakram optik tersebut. Hampir dapat dipastikan hari ini, pemanfaatan teknologi tersebut telah dilakukan secara besar-besaran oleh produser rekaman illegal di Indonesia. Jika ditelusuri di seluruh gerai-gerai pedagang kaki lima, penjualan VCD dan DVD hasil karya sinematografi dapat dipastikan 90% bersumber dari produser-produser illegal. Dari 188 responden kalangan gerai pedagang kaki lima dan pedagang outlet di plaza-plaza yang diteliti, 169 responden menjawab menjual VCD dan DVD non original (istilah lain untuk menyebutkan VCD dan DVD hasil bajakan), sedangkan 19 responden lainnya menjawab menjual VCD dan DVD original seperti tertera pada tabel di bawah ini. Tabel 3 Legalitas Barang-barang yang Dijual No 1. 2. Keterangan Original/legal Non Original/illegal Total Sumber : Data Primer Frekwensi 19 169 188 Persentase 10,10 % 89,90 % 100 % Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa hanya 10,10 % saja para pedagang yang menjual VCD dan DVD karya sinematografi yang original. Selebihnya sebanyak 89,90 % dari para pedagang menjual VCD non original. Data tersebut di atas mengungkapkan betapa kecaunya dan lemahnya penegakan hukum hak cipta Nasional untuk karya sinematografi. Mulai dari substansi hukumnya, struktur sampai pada kultur hukumnya tidak mendukung untuk terwujudnya upaya menumbuhkan kreativitas pencipta, khususnya di lapangan karya 422 sinematografi. Sekalipun delik yang diancamkan merupkana delik pidana biasa, tak ada tindakan hukum langsung yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Dalam serangkaian wawancara dengan salah seorang pedagang345 terungkap bahwa; Pernah diadakan semacam razia, tapi bukan fokus pada VCD dan DVD bajakan, tapi yang berhubungan dengan pornografi. Apakah kami ada menjual VCD dan DVD dalam istilahnya Blue Film. Kami tak pernah dipersoalkan tentang VCD dan DVD bajakan, walaupun kami mengetahui perbuatan itu salah. Tapi sepertinya aparat yang melakukan razia spertinya “mengerti’ keadaan itu. Sehingga kamipun harus memberikan “sesuatu” juga. Pada saat razia kami memang tidak menampilkan barang dagangan kami secara keseluruhan, hanya sebahagian saja. Kami khawatir juga bila ada penyitaan. Selepas itu kami kami kembali kembali menggelar barang dagangan kami. Signal yang digambarkan oleh pedagang ini, memang sampailah pada uraian akhir tuluisan ini. Faktor prilaku budaya hukumlah yang sangat berpengaruh pada penegakan hukum di samping dua faktor yang lainnya, substansi dan struktur. Ketika aparat kepokisian melakukan razia, pedagang-pedagang terlihat tertib dan patuh, tapi selepas itu mereka kembali melakukan aksi bisnisnya. Seperti kata pepatah, Anjing menggonggong kafilah pun berlalu. Tak ada kesan yang tinggal untuk memeprbaiki kesalahan atau sekedar mengingat bahwa dalam aktivitas mereka ada hak-hak orang lain yang dilanggar. Kelihatannya mengambil hak orang lain untuk memperoleh keuntungan sendiri sebenarnya dilarang oleh agama apapun dan secara moral dianggap sebuah pelanggaran moral serta secara etika perbuatan itu sangat tidak etis sekalipun si pemiliknya tidak mengetahuinya. Pesan Al-Qur’an mengingatkan, Allah berfirman, janganlah kamu mengira ketika kamu berbuat kesalahan yang tidak diketahui orang lain kamu mengira hanya kamu sendiri yang tahu, sesungguhnya kamu berdua, yang satu lagi adalah Aku. Pada ayat lain Allah mengatakan: sesungguhnya Aku mengetahui apa yang nyata dan apa yang tersembunyi di hati manusia. Inilah asas “pengawasan melekat” yang seharusnya ditanamkan di setiap hati sanubari manusia, hati sanubari anak bangsa yang meletakkan dasar Ketuhanan pada sila pertama Pancasila sebagai Asas Pembangunan Nasional termasuk azas Politik Pembangunan Hukum Nasional. 345 Pukul 11.20. Wawancara dengan SM di Medan, tanggal 10 November 2012, di Medan, 423 4. Budaya Hukum Masyarakat Ada apa dengan prilaku hukum (budaya hukum) masyarakat ?Masyarakat produsen dan masyarakat konsumen sama-sama melakukan tindakan pelanggaran atas karya sinematografi. Apakah sudah sedemikian burukkah prilaku hukum masyarakat yang berlangsung selama ini, sehingga tak satupun lagi anggota masyarakat dapat memberikan apresiasi atau penghargaan atas karya cipta orang lain? Sebuah fenomena yang menarik yang sedang berlangsung di tengah-tengah masyarakat Indonesia dalam hal bertransaksi adalah, jika ada yang lebih murah buat apa beli yang lebih mahal, persis seperti iklan racun serangga. Sekalipun harga yang murah itu, dibelakangnya terdapat hak orang lain. Memang di berbagai kasus pelanggaran HKI, jika suatu produk dapat meniadakan pembayaran royalty dari pemegang hak, produk itu dapat dijual dengan harga yang lebih murah jika dibandingkan dengan produk yang sama, tapi dikenakan pembayaran royalti. Buku-buku hasil bajakan-pun banyak dijual dengan harga murah jika dibandingkan dengan buku yang original yang dicetak oleh penerbit yang resmi mendapatkan izin untuk memperbanyak atau penggandaan dari pencipta. Begitu juga untuk kasus DVD dan VCD hasil bajakan, akan dijual lebih murah, sehingga para konsumen cenderung untuk membeli hasil bajakan atau produk illegal. Semua responden yang diteliti, menjawab lebih suka membeli barang hasil bajakan seperti tertera pada tabel di bawah ini. Tabel 4 Kecenderungan Konsumen membeli VCD dan DVD Hasil Bajakan. No 1. 2. Keterangan VCD/DVD original VCD/DVD non original Total Sumber : Data Primer Frekwensi 0 188 Persentase 0% 100 % 188 100 % Tabel di atas memperlihatkan dari total 188 responden, semuanya atau 100% memilih lebih suka berbelanja atau membeli VCD dab DVD non original (barang illegal). Alasannya adalah karena VCD dan DVD itu hanya ditonton untuk masa putar satu kali saja. 424 Kualitasnya juga ternyata tidak jauh berbeda dengan yang original, sementara harga yang original jauh lebih mahal. Ketika ditanyakan apakah mereka pernah membeli VCD dan DVD yang original? Sebanyak 48 responden atau 26,67% menyatakan pernah membeli barang yang original, sedangkan selebihnya sebanyak 140 responden atau sekitar 73,33% menyatakan tidak pernah membeli barang yang original, seperti tertera pada tabel berikut ini. Tabel 5 Pilihan Konsumen Untuk Membeli Barang Legal dan Illegal No 1. 2. Keterangan VCD/DVD original VCD/DVD original Total Sumber : Data Primer non Frekwensi 48 140 188 Persentase 25,53 % 74,47 % 100 % Alasan mereka membeli barang yang original adalah karena, film ceritanya masih baru belum ada bajakannya (maksudnya film cerita serupa belum ada yang diproduksi dalam bentuk illegal,pen). Sementara itu mereka yang tak pernah membeli barang yang original mengatakan, harganya terlalu mahal, sampai 20 kali lipat. Artinya 1 keping VCD atau DVD original harganya sama dengan 20 keping yang non original. Tingkat pengetahuan masyarakat konsumen terhadap aspek hukum perlindungan karya sinematografi, ternyata hanya sebahagian saja yang mengetahui. Bahwa hasil bajakan itu adalah tindakan illegal dan dapat diancam hukuman pidana. Dari 188 responden, ternyata 68 responden atau sekitar 36,17 % mengatakan mengetahui bahwa penjualan barang-barang berupa VCD dan DVD bajakan itu adalah perbuatan illegal, melanggar hukum dan dapat diancam dengan hukuman pidana, akan tetapi 112 responden atau sekitar 63,83 % mengatakan tidak mengetahui sama sekali, seperti tertera pada tabel di bawah ini : 425 Tabel 6 Tingkat Pengetahuan Konsumen Terhadap Aspek Hukum Pembajakan Karya Sinematografi No 1. Keterangan Mengetahui Frekwensi 68 2. Tidak mengetahui 120 Total Sumber : Data Primer 188 Persentase 36,17 % 63,83 % 100 % Ketika ditanyakan, (khusus bagi mereka yang mengetahui bahwa perbuatan itu adalah perbuatan illegal) apakah mereka tidak takut dengan ancaman hukuman ? Ternyata dari 68 responden yang menyatakan mengetahui bahwa perbuatan itu adalah illegal diluar dugaan mereka memberi jawaban; tak pernah ada tindakan hukum untuk perbuatan membeli barang VCD dan DVD bajakan. Seluruh responden yang mengetahui tentang itu yakni 68 responden atau 100 % menyatakan tak pernah ada tindakan hukum dari aparat penegak hukum, seperti tertera pada tabel berikut ini. Tabel 7 Tindakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Aparat Terhadap Konsumen Yang membeli Produk VCD dan DVD Illegal No 1. Keterangan Melakukan tindakan hukum 2. Tidak melakukan tindakan hukum Total Sumber : Data Primer Frekwensi 0 Persentase 0% 68 100 % 68 100 % Tak ada tindakan hukum dari aparat penegak hukum yang dilakukan untuk konsumen yang membeli barang berupa VCD atau DVD bajakan. Jangankan untuk kalangan konsumen untuk kalangan pedagang atau penjualpun tindakan yang sama juga tidak pernah ada dilakukan selama 1 tahun terakhir. Padahal lebih dari 80 % barang 426 yang dijual adalah barang illegal hasil perbuatan melanggar hukum, sebagaimana diberitakan oleh banyak media massa. Dalam wawancara dengan seorang hakim di Pengadilan Negeri Medan 346 diperoleh tanggapan tentang pelanggaran VCD dan DVD illegal marak dimana-mana, beliau mengatakan : Ini salah satu bentuk lemahnya penegakan hukum kita, kita selalu saja lambat mengantisipasi terjadi pelanggaran hukum, nanti kalau sudah heboh dan banyak desakan, baru semua kelabakan. Semestinya pelanggaran hak cipta ini bisa diantisipasi, bisa dimulai dengan razia di tingkat pengecer, kemudian dilakukan pengembangan terhadap pelaku-pelaku yang terlibat dalam pelanggaran terhadap karya cipta ini. Kita punya Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, mestinya ini bisa diimplementasi oleh orangorang yang terlibat didalam undang-undang ini, kedepannya kalaulah ini tak bisa diselesaikan maka dikhawatirkan karya-karya anak-anak bangsa ini semakin menurun. Selanjutnya dalam wawancara dengan seorang hakim di Pengadilan Negeri Medan 347 juga diperoleh keterangan bahwa : Faktor dominan kenapa kaset bajakan ini masih banyak beredar karena faktor masih lemahnya penegakan hukum kita dalam memberantas peredaran kaset VCD dan DVD bajakan. Selain itu juga faktor ekonomi yang masih mahalnya harga VCD dan DVD original juga merupakan faktor yang dominan terhadap munculnya pembajakan kaset disamping juga faktor sosial budaya dan pendidikan, sehingga upaya penanggulangan pembajakan kaset belum dilaksanakan secara maksimal karena masih banyak ditemukan adanya produk-produk kaset bajakan yang dijual di masyarakat. Penegakan hukum kita dalam upaya memberantas kaset bajakan masih bersifat parsial, belum komprehensif. Hakim348 tersebut menjelaskan pula bahwa : Penegakan hukum bukan satu-satunya upaya yang ampuh dalam memberikan perlindungan hak cipta ini, karena penegakan hukum hanya bagian dari sebuah proses perlindungan. Penegakan hukum hanya merupakan sub-sistem yang bersifat represif dari sebuah sistem perlindungan. Sub sistem lain yang sama pentingnya adalah sub sistem pre-emtif dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat termasuk aparat pemerintah dan penegak hukum, ketersediaan dan kemampuan daya beli masyarakat. Di samping itu juga upaya preventif menjadi bagian dari upaya pencegahan dalam rangka mempersempit peluang terjadinya proses pelanggaran, seperti tidak memberikan ijin kepada took atau kaki lima yang telah melanggar atau mencabut ijin pabrik yang pernah melanggar. 346 Wawancara dengan salah seorang hakim di PN Medan, Surya Pardamaian, SH, tgl 5 September 2013, pukul 10.00 di Medan. 347 Wawancara dengan salah seorang hakim di PN Medan, Indra Cahya, SH, MH, tgl 5 September 2013, pukul 11.00 di Medan. 348 Ibid. 427 Masih wawancara dengan salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Medan 349 dinyatakan bahwa : Permasalahan pembajakan terhadap karya cipta baik itu dalam bentuk VCD maupun DVD harus ditangani secara serius dan komprehensip, kalaulah ini dibiarkan bisa menjadi bom waktu. Kita sebenarnya sudah ada undang-undang hak cipta yang pada intinya melindungi hasil karya pengiat seniman kita dan ini sebenarnya bisa menjadi paying hukum untuk melindungi karya cipta ketika terjadi pelanggaran dari undang-undang tersebut. Memang dalam implementasi dilapangan tidaklah semua harus mesti sampai ke ranah pengadilan, harus ada upaya persuasif sebelum masuk ke ranah hukum, misalnya diperlukan sosialisasi, razia VCD bajakan dan lain-lain. Pelanggaran terhadap hak cipta seperti VCD dan DVD bajakan itu dalam undang-undang No. 19 Tahun 2002 dikategorikan sebagai delik biasa. Dalam wawancara dengan salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Medan 350 diperoleh tanggapan bahwa : Ini bukan masalah perbuatan delik biasa atau tidak, jika memang amanah undang-undang mengatur bahwa jika ada pelanggaran terhadap hak cipta, maka pelakunya harus diproses. Pihak polisi harus lebih proaktif, jangan mesti menunggu bola, harus ke lapangan melakukan sosialisasi dan merazia bagi pedagang-pedagang sebagai upaya pembelajaran bagi mereka. Kalaulah ini sudah dilakukan dan tidak berdampak, maka pihak polisi harus melakukan upaya hukum. Tetapi juga sangat semuanya diserahkan kepada polisi, pihakpihak terkait harus mensuport atas kerja-kerja polisi dan menangani perkara ini. Semua elemen harus ikut terlibat dalam mencegah pelanggaran-pelanggaran hak cipta, tidak semuanya permasalahan ini ditumpukkan hanya kepada aparat penegak hukum saja terutama polisi. Penggiat-penggiat seni juga harus memberikan kontribusi, jangan asal bicara saja, perlu juga ada upaya tindakan-tindakan untuk mencegah terjadi pelanggaran ini. Masyarakat harus diberi pemahaman yang lebih dalam tentang undang-undang No. 19 Tahun 2002. Para pedagang baik di gerai-gerai kaki lima atau gerai di plaza-plaza sebagaian besar menjual VCD dan DVD karya sinematografi illegal. Anggapan yang selama ini muncul dalam pemberitaan pada berbagai media yang dirilis dari penjelasan berbagai asosiasi produser rekaman dan kalangan dunia perfilman ternyata benar. Dapat dipastikan VCD dan DVD yang beredar di kalangan pedagang adalah lebih dari 80% hasil bajakan atau hasil pelanggaran hak cipta. Data di atas, selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suyud Margono yang mengatakan, “bahwa lebih dari 80% hasil 349 Wawancara dengan salah seorang hakim di PN Medan, Baslin Sinaga, SH, tgl 5 September 2013, pukul 12.00 di Medan. 350 Ibid. 428 karya sinematografi yang beredar di pasar lokal Indonesia adalah merupakan hasil bajakan atau hasil pelanggaran hak cipta”. 351 Ancaman hukuman atas pembajakan hak cipta pada setiap kali perubahan undang-undang hak cipta dari waktu ke waktu mengalami kenaikan, layaknya seperti inflasi dalam dunia usaha. Kenaikan ancaman hukuman itu karena banyaknya rekomendasi dari berbagai pihak yang mengatakan pembajakan hak cipta itu berlangsung karena ancaman hukuman pidananya terlalu rendah. Anggapan seperti itu justeru muncul dari kalangan negara-negara industri maju yang dimotori oleh Amerika yang diikuti oleh negara-negara Eropa dengan menyampaikan pandangan yang sama. Karena alasan itulah kemudian ancaman hukuman pidana terhadap pelanggaran hak cipta terusmenerus mengalami perubahan dan semakin diperberat,dari waktu ke waktu dalam empat kali kurun waktu perubahan undang-undang hak cipta nasional, akan tetapi itu tidak juga membuat jera pelaku pembajakan di Indonesia namun justru sebaliknya praktek pembajakan terus berlangsung. Tak ada juga pihak-pihak yang merasa takut atau dalam bahasa hukum pidana merasa tercegah (preventif) dengan tingginya ancaman hukuman itu. Pihak produsen karya sinematografi illegal terus-menerus memproduksi karya cipta itu dalam bentuk kepingan VCD dan DVD bahkan sekarang dikenal ada produksi dalam bentuk blue ray. Hasil observasi yang dilakukan di gerai penjualan VCD dan DVD di Jalan Dr. Mansyur, Jalan Setia Budi dan Jalan Titi Papan membuktikan bahwa produser illegal setiap sore memasok hasil-hasil produksinya ke gerai-gerai tersebut. 352 Para konsumen juga datang berbelanja silih berganti, dan paling sedikit berbelanja 3-10 keping. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa takut bahwa tindakan mereka adalah merupakan perbuatan pidana yang dapat diancam dengan hukuman pidana. Pihak pemilik karya sinematografi pun tak mempunyai kuasa yang cukup untuk menghentikan aktivitas pembajakan tersebut, tidak juga pihak Amerika atau negara-negara maju yang secara terus menerus bersikeras untuk penegakan hukum hak cipta di Indonesia. Justru karya sinematografi yang terbanyak dibajak itu adalah karya sinematografi milik asing. Berdasarkan 351 Maraknya pembajakan hak cipta di Indonesia ternyata berimplikasi panjang. Setelah keluar dari Priority Watch List oleh Amerika Serikat atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tahun 2000, sejak April 2001, Indonesia masuk kembali daftar hitam pelanggaran hak cipta ini. Disamping pembajakan karya musik lagu, film dalam bentuk CD dan VCD, program komputer juga salah satu yang paling terbesar dibajak. Lebih lanjut lihat Suyud Margono, Op.Cit, hal. 146. 352 Pada setiap sore sekitar pukul 16.00 Wib, pada bulan Juni 2012 kami menyaksikan VCD dan DVC bajakan itu dipasok melalui kurir mengendarai kendaraan bermotor dan dingkus dalam plastic yang diperkirakan tidak kurang dari 100 keping dengan berbagai judul film. 429 kuisioner yang diedarkan tercatat bahwa pada 188 gerai yang menjual karya sinematografi hasil bajakan, tercatat film Amerika dijual di 112 gerai, film Korea dijual di 75 gerai, film India dijual di 67 gerai sebagaimana tertera pada grafik di bawah ini. Grafik : 2 Karya Sinematografi Bajakan Yang Diperdagangkan di Gerai Tradisional di Kota Medan 112 75 67 62 49 45 40 17 15 16 20 7 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2 3 Amerika Amerika Latin Eropa Hongkong/Cina India Korea Sumber : Data Primer 4 5 6 7 8 9 10 7. Jepang 8. Pilipina 9. Prancis 10. Malaysia 11. Indonesia 12. Mandarin 11 12 430 Pembajakan karya sinematografi menurut Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dilakukan oleh orang-orang tertentu yang berasal dari industri rumahan dan ini sangat berbahaya sekaligus merupakan ancaman industri kreatif perfilman nasional. 353 Saat ini semakin sulit untuk dicegah aktivitas industri pembajakan karya sinematografi karena kemajuan teknologi pemindaian yang dapat diakses dari jaringan internet dan didukung oleh teknologi rekaman yang menggunakan serat optik. 354 Kalangan konsumen juga tidak pernah merasa bersalah atau ada pihak-pihak yang mempersalahkannya jika menikmati hasil karya sinematografi dengan cara membeli dengan harga murah. Tidak pernah terlintas dalam pikiran para konsumen bahwa di atas kenikmatan yang ia peroleh terdapat hak-hak orang lain yang ia langgar. Pihak aparat kepolisian pun sekalipun telah mengetahui delik pelanggaran hak cipta itu adalah delik biasa akan tetapi tidak pernah melakukan tindakan penyidikan dalam arti menerapkan pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai perbuatan pidana tertangkap tangan. Perlakuan ini berbeda ketika seseorang diketahui mengedarkan obatobat terlarang, tindakan cepat langsung dilakukan oleh aparat penyidik. Tidak menarik memang jika kasus pelanggaran hak cipta segera ditangani melalui upaya penegakan hukum pidana. Aparat penyidik 353 Penjelasan Wihadi Wianto, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Rekaman Video Indonesia (Asirevi), dalam Kompas, Pembajakan Film Nasional Ditengarai Industri Rumahan, Jumat, 23 Oktober 2009. Menurut Ketua Lembaga Koordinasi Gerakan Anti Pembajakan, Togar Sianipar, pada Februari 2013 di Jakarta terdapat 2,1 juta keping cakram film dan musik hasil bajakan dengan kerugian triliunan rupiah di pihak pencipta, Lebih lanjut lihat indosiar.com, Negara Dirugikan Triliunan Rupiah Pembajakan Hak Intelektual, Februari 2013. 354 Cakram optik ini adalah sarana yang diciptakan untuk dapat menyimpan dan/atau memperbanyak ciptaan atau karya cipta dalam bentuk cakram plastik atau piringan terhadap gambar, suara dan teks. Cakram tersebut merupakan format sinar laser. Penemuan yang ini berkaitan dengan cakram video rekaman yang memiliki kemampuan memperbanyak atau menggandakan rekaman secara massal dengan menggunakan sebuah cakram master. Cakram yang terbuat dari plastik transparan tersebut mampu menyimpan informasi gambar dalam bentuk sinyal-sinyal video yang direkam pada salah satu atau kedua sisi cakram. Informasi gambar yang telah direkam dimaksudkan untuk ditampilkan ulang, misalnya melalui pesawat televisi dengan menggunakan alat pemutar cakram dan dengan ”menembakkan” pancaran sinar elektron melalui cakram tersebut. Pancaran sinar ini disesuaikan dengan rekaman video yang telah tersimpan dalam cakram dan head alat pemutar mengubah sinyal-sinyal sinar tersebut menjadi sinyal-sinyal video atau sinyalsinyal gambar agar dapat ditayangkan ulang pada layar monitor. Lebih lanjut lihat Kenny Wiston dan Toto S. Mondong, Optical Disc-Sarana Mempermudah Perbanyakan Karya Cipta Tantangan Bagi Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta, Buletin HKI Volume 4 No. 1 Juli 2003, hal. 8. 431 sebagian besar enggan untuk melakukan penyidikan karena tindak pidana semacam itu adalah tindak pidana yang tidak mengangkat popularitas mereka sebagai aparat penyidik. Akibatnya secara terangterangan karya sinematografi bajakan itu beredar di pasaran. Karyakarya sinematografi yang paling banyak terjual masih didominasi oleh film Amerika dan diikuti film Korea, film India dan Eropa. Grafik : 3 Karya Sinematografi Bajakan Yang Paling Banyak Terjual di Gerai Tradisional di Kota Medan 99 63 40 42 27 37 23 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2 7 5 10 3 Amerika Amerika Latin Eropa Hongkong/Cina India Korea Sumber : Data Primer 4 5 6 7 8 9 7. Jepang 8. Pilipina 9. Prancis 10. Malaysia 11. Indonesia 12. Mandarin 11 10 6 11 12 432 Grafik di atas mengantarkan pada satu kesimpulan bahwa produksi film Amerika-lah yang paling banyak dibajak di Indonesia, karena itu wajar saja jika kemudian pihak Amerika mendesak agar Indonesia serius dalam penegakan hukum hak cipta. Keseriusan itu oleh lembaga pembuat Undang-undang disikapi secara keliru yakni dengan menaikkan ancaman pidana dan menempatkan delik pelanggaran hak cipta sebagai delik biasa. Sudah saatnya delik pelanggaran hak cipta itu diubah kembali menjadi delik aduan, dengan demikian pihak yang diruigikan dapat mengadukan perbuatan itu kepada lembaga kepolisian untuk segera dilakukan penyidikan, lalu kemudian pihak pengadu dapat mengontrol jalannya perkara. Dengan katagori delik aduan di samping dapat mengatasi proses pembiaran yang dilakukan oleh aparat penyidik selama ini, juga perkara ini dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat (pemenuhan nilai-nilai asas sila ke- 4 Pancasila) antara pihak yang melakukan pelanggaran dengan pihak yang dirugikan, karena perkara ini dapat diakhiri dengan pencabutan pengaduan oleh pihak yang dirugikan atau pihak pengadu. Film-film box office yang banyak diminati oleh konsumen sekaligus yang banyak diproduksi secara illegal masih didominasi oleh film-film Amerika. Bahkan film-film yang dijual di konter illegal itu film-film terbaru dan lebih lengkap jika dibandingkan dengan pedagang yang menjual di konter-konter yang legal. Untuk alasan itulah kemudian salah seorang dari responden itu mengatakan dalam sebuah wawancara. 355 Saya sudah lebih dari 5 tahun berbelanja VCD dan DVD ini, kebanyakan yang saya beli barang-barang non original.Ada juga barang yang original, akan tetapi kualitasnya tidak jauh berbeda, sehingga sekarang saya tak pernah lagi membeli barang yang original. Saya mengetahui barang-barang nonoriginal itu adalah hasil perbuatan illegal, sebab sayapun lulusan Fakultas hukum. Tapi mengapa saya justeru membeli barang yang illegal, alasan lebih dari pada sekedar murah dan kualitas bagus. Konter-konter yang menjual VCD dan DVD bajakan itu menjual film cerita yang lebih lengkap. Di konter-konter yang menjual barang original, terutama-terutama di plaza-plaza ternyata barang-barang yang dijual sangat terbatas, dan film “jadul” lagi (maksudnya, film cerita yang sudah usang, ketinggalan zaman), sementara di konter-konter yang menjual barang illegal, banyak ditawarkan film-film terbaru. Saya sendiri sekarang punya langganan konter khusus di Jalan Dokter Mansyur simpang Setia Budi. Kalau DVD yang saya beli “nyangkut” dalam arti tampilan gambar tidak bagus atau “macet” dapat ditukar. 355 Wawancara dengan SS, tanggal 14 September, pukul 16.15, di Medan. 433 Wawancara di atas memperlihatkan betapa kompleksitasnya sudah hubungan antara pedagang DVD bajakan dengan konsumen. Bahkan ada semacam pelayanan “purna jual”. Tentu saja kenyataan empirik semacam itu telah menjadi prilaku yang lazim dalam hubungan hukum sehari-hari saat ini dan di kemudian hari kelak. Budaya (hukum) permisif kelihatannya telah masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan. Oleh karena terjadi proses “pembiaran” secara struktural, maka simbolsimbol pelanggaran hukum itu berubah menjadi kebiasaan yang lazim dan tidak lagi dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum, meskipun norma hukum yang mengancam perbuatan itu masih berlaku. Di satu sisi undang-undang hak cipta nasional telah mengkriminalisasikan masyarakat, namun di sisi lain struktur dan kultur telah “membatalkan” norma hukum itu secara diam-diam. Akhir dari sebuah perjalanan penegakan hukum dalam lapangan karya cipta sinematografi adalah, berpangkal pada pilihan politik hukum pragmatis dengan cara transplantasi dan model kodifikasi parsial dan berujung pada penegakan hukum yang terhenti. E. Penegakan Hukum Hak Cipta Dalam Bidang Sinematografi Kekacauan sistem hukum hak cipta nasional terlihat nyata dalam urai-uraian terdahulu. Secara substansi norma hukum undangundang hak cipta Nasional sebahagian jauh dari nilai-nilai filosofis Pancasila. Dalam tatanan struktur, ditandai dengan birokrasi lembaga pembuat undang-undang dan birokrasi lembaga peradilan yang korup. Dalam tataran budaya hukum, tidak adanya faktor-faktor budaya hukum yang mendukung bagi terciptanya iklim penegakan hukum dalam satu tatanan (sistem) yang kompak. Kesemua ini akan membawa dampak bagi pertumbuhan industeri perfilman nasional sebagai wujud dari karya cipta sinematografi. 356 Karya cipta sinematografi adalah pencerminan sebuah peradaban. Dalam melahirkan karya sinematogri tidak hanya melibatkan sutradara, aktor dan juru kamera, akan tetapi diawali dari ide atau gagasan sebuah cerita yang dituangkan dalam bentuk visualisasi yakni dalam bentuk gambar dua dimensi yang bergerak. Sebuah ide atau gagasan adalah sebuah hasil karya dalam bidang kesusasteraan, bisa dalam bentuk kisah nyata, atau sebuah sejarah yang didokumentasikan. Tak jarang pula karya sinematografi itu berupa 356 Istilah karya sinematografi, ditemukan dalam berbagai-bagai frase seperti, karya film atau bioskop. Kata film lebih dimaknai pada jenis atau bahan yang digunakan untuk menangkap gambar, sedang frase “bioskop” berasal dari kata “bio” yang berarti hidup, “scope” yang berarti gambar. 434 sebuah film cerita semi dokumenter. Dalam karya sinematografi ide atau gagasan cerita penghianatan, mafia hukum, peperangan, drama rumah tangga, sejarah dan lain-lain yang menggambarkan peradaban umat manusia. Gambaran karya sinematografi yang dihasilkan sebagai sebuah karya akan tampak tercermin dari peradaban bangsa itu. Pada masa di mana hak azasi manusia tidak dilindungi dengan baik, produk karya sinematografi tidak akan memunculkan issu atau tema cerita tentang itu. Banyak karya sastra dan karya sinematografi yang dicekal oleh pemerintah hanya karena karya itu tidak sejalan dengan keinginan penguasa. Banyak juga karya sinematografi yang diproduksi bertentangan dengan fakta sejarah, hingga akhirnya ketika penggantian rezim kekuasaan karya itu tidak dimunculkan lagi. 357 Dalam penjelasan Pasal 12 huruf (k) Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa sinematografi merupakan media komunikasi massa gambar gerak (moving images) antara lain meliputi : film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dalam pita seluloid, piringan video, pita video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, di layar lebar atau ditayangkan di televisi atau di media lainnya. Karya sinematografi sendiri berasal dari Bahasa Inggris ”cinematography” yang asal katanya bersumber dari Bahasa Latin yaitu ”cinema” yang artinya gambar. Dalam pengertian umum sinematografi adalah segala hal mengenai sinema (perfilman) baik dari estetika, bentuk, fungsi, makna, produksi, proses, maupun penontonnya. Dunia sinematografi dalam hal ini menyangkut pemahaman estetik melalui paduan seni akting, fotografi, teknologi optik, komunikasi visual, industri perfilman, ide, cita-cita dan imajinasi yang sangat kompleks. Pemahaman estetika dalam seni (secara luas), bentuk pelaksanaannya merupakan apresiasi. Apresiasi seni merupakan proses sadar yang dilakukan penghayatan dalam menghadapi karya seni (termasuk film). Sinema (perfilman) merupakan sebuah proses kreatif, ada ekspresi/ide, ada simulasi peristiwa dan menimbulkan apresiasi. Sedangkan obyek dalam film terdapat aspek material yang harus dipahami seperti medium celluloid, serat optik dalam compact disk (audio), video compact disc (audio dan visual) dan lain-lain. Aspek formal berbentuk gambar, gambaran ruang dan waktu secara virtual 357 Film G30S PKI misalnya tidak lagi ditampailkan di media elektronik pada setiap tanggal 30 September, karena dianggap film itu penuh dengan kebohongan dan hanya untuk menampilkan kepahlawanan Soeharto. 435 dan film dibuat berdasarkan penyusunan skenario yang didasarkan atas ide kehidupan manusia secara virtual. 358 Di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman disebutkan bahwa yang dimaksud dengan film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik atau proses lainnya, dengan atau tapa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik dan/atau lainnya. 359 Karya sinematografi sering diidentikkan dengan kata ”film”, terkait sejarahnya di mana pertama sekali media penyimpanan dari karya sinematografi tersebut adalah memakai pita film (pita seluloid) yaitu sejenis bahan plastik tipis yang dilapisi zat peka cahaya. Alat inilah yang dipakai sebagai media penyimpan di awal pertumbuhan industri sinematografi tersebut. Media penyimpanan (perekaman) itu sendiri kemudian berkembang mengikuti perkembangan teknologi seperti antara lain memakai cakram optik dalam compact disk (audio), video compact disc (audio dan visual). 360 Terkait dengan penelitian ini maka yang menjadi obyek pembahasan adalah karya sinematografi dengan medium penyimpanan cakram optik padat video yang dikenal dengan Video Compact Disc (DVD dan VCD) atau dalam penelitian ini disebut karya sinematografi dalam bentuk DVD dan VCD. Rekaman video yang dikenal di Indonesia pada awalnya adalah video kaset yang beredar di tahun 1980an hingga awal tahun 1990-an. Keberadaan video kaset ini kemudian menghilang seiring dengan munculnya teknologi Laser Disc di awal tahun 1990-an. Pada perkembangan selanjutnya, keberadaan laser disc ini juga tidak bertahan lama, ketika pada tahun 1995 mulai masuk format baru, yaitu DVD dan VCD yang sebenarnya secara kualitas jauh di bawah laser disc. Namun demikian dengan harga yang relatif lebih murah, keberadaan DVD dan VCD ini secara perlahan hingga kemudian pada tahun 1997 berhasil menggeser format Laser Disc dari peredaran rekaman video di Indonesia. Karya sinematografi tidak bisa dimaknai hanya sebagai sebuah karya untuk semata-mata dijadikan sebagai kepentingan hiburan. Akan tetapi karya sinematografi sarat dengan pesan-pesan sejarah dan pesanpesan budaya. Ada kalanya karya sinematografi mungkin tidak 358 Pengertian ini sebagaimana dijelaskan dalam http://duniasinematografi.blogspot.com, diakses tanggal 12 Februari 2013. 359 Sebagaimana rumusan di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman. 360 Ibid. 436 memiliki makna pada hari ini, akan tetapi karya itu menjadi sangat berharga untuk masa-masa yang akan datang. Bagaimana kita mengenal budaya Betawi pada masa lalu, film Si Doel Anak Sekolahan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan di atas. Begitulah ketika suatu masa untuk dapat memahami situasi menjelang kemerdekaan, film-film dokumenter dapat memberikan gambaran tentang keadaan itu. Kemajuan peradaban suatu bangsa pun dan pilihan-pilihan budaya yang dilakukan oleh masyarakatnya juga dapat direkam dengan baik dari cerita-cerita karya sinematografi yang dilahirkan pada zamannya. Ketika masyarakat Indonesia tumbuh dalam peradaban hedonisme, karya-karya sinematografi yang muncul menampilkan cermin peradaban masyarakat hedonis itu. Sehingga dari jalan cerita film itu sangat mudah untuk dikenali, pada priode atau zaman apa karya sinematografi itu diproduksi. Semakin maju peradaban bangsa itu semakin tampak dengan jelas kemajuan itu terekam dalam karya sinematografi. 361 Karya sinematografi pertama kali diproduksi pada tahun 1926, sebuah film bisu yang tertinggal secara teknologi, sebab di belahan dunia yang lain telah diproduksi film-film yang bersuara terutama di Eropa, Amerika dan Cina pada periode yang sama. 362 Film lokal pertama yang berjudul ”Loetoeng Kasarung” itu dimainkan oleh artisartis pribumi. Produksi film perdana itu adalah awal dari tonggak sejarah munculnya industri perfilman nasional, karena itu bermunculanlah produser-produser film lokal di wilayah nusantara. Produksi film Indonesia mengalami masa jaya pada tahun 1941 yang menghasilkan 41 judul film, serta melahirkan pemainpemain terkenal seperti Roekiah, Rd Mochtar dan Fifi Young. 363 Akan tetapi surut kembali pada masa-masa awal penjajahan Jepang yang disusul dengan penurunan secara drastis produksi film lokal secara kuantitatif. Hal tersebut terjadi karena film-film yang boleh diputar hanyalah film dokumenter yang menampilkan kegagahan Jepang dan sekutunya. Intervensi politik dalam kebudayaan pun terasa kental 361 Dahulu ketika teknologi sinematografi ditemukan di Amerika dan Prancis pada akhir abad 19, Indonesia masih merupakan koloni Belanda. dan belum mengenal karya sinematografi. Baru pada tahun 1900, ada karya sinematografi yang dipertontonkan di wilayah Hindia Belanda berupa film impor dan film dokumentasi dari Eropa. Tahun 1905 baru muncul film cerita diimpor dari Amerika dan Cina, itupun masih dalam wujud film bisu sampai dengan tahun 1923. Lebih lanjut lihat Misbach Yusa Biran, Perkenalan Selintas Mengenai Perkembangan Film di Indonesia Asia University, Tokyo, 1990, hal. 1. Industri karya sinematografi terus berkembang berkat penemuan teknologi itu dan film pertama kali dipertontonkan untuk khalayak umum, berlangsung di Paris, Perancis pada tanggal 28 Desember 1895 yang sekaligus menandai lahirnya film (bioskop) di dunia. Lebih lanjut lihat Viktor C. Mambor, “satu abad” “Gambar Idoep” di Indonesia, diakses dari http://kunci.or.id/victorI.htm, pada tanggal 5 Februari 2013. 362 Victor C. Mambor, Loc.Cit. 363 Misbach Yusa Biran, Opcit, hal. 11. 437 ketika Jepang melarang diedarkannya film yang diproduksi oleh negara pemenang perang seperti Amerika dan sekutu-sekutunya. 364 Pertumbuhan film Indonesia sejak tahun-tahun pertama industri perfilman lokal dimulai yakni pada tahun 1926 hingga tahun 1932 dapat dilihat pada matrik di bawah ini. Matrik 40 Film Produksi Tahun 1926-1932 Tahun 1926 Judul Film Loetoeng Kasaroeng Sutradara L. Heuveldorp 1927 1928 Eulis Atjih Lily van Java Resia Boroboedoer Berloemoer Darah Njai Dasima (I) Rampok Preanger Si Tjomat Njai Siti / Des Stem das Bloed Karnadi Anemer Bangkok Lari Ka Arab Melati van Agam I, II Njai Dasima II, III Si Ronda Atma De Vischer (bersuara) Bung Roos van Tjikembang Indonesia Melaise Sam Pek Eng Tay Si Pitoeng Sinjo Tjo Main di Film Karina’s Zelfopoffering Njai Dasima (bicara) Raonah Terpaksa Menika (bicaramusik) Zuster Therisia L. Heuveldorp Nelson Wong Nelson Wong Tidak tercatat Lie Tek Swie Nelson Wong Nelson Wong Ph. Carli Dukungan Dana Pemerintah Kota Bandung Pinjaman obligasi Taipan Surabaya Batavia Motion Picture Tan Boe Soan Tan’s Film Halimoen Film Batavia Motion Picture Cosmos Film Corps G. Krugers Wong Bersaudara Lie Tek Swie Lie Tek Swie Lie Tek Swie G. Krugers Krugers Film Bedrijf Halimoen Film Tan’s Film Tan’s Film Tan’s Film Krugers Film Bedrijf The Teng Chun Cino Motion Pictures Wong Bersaudara The Teng Chun Wong Bersaudara M.H. Schiling Ph. Carli Bachtiar Effendy G. Krugers G. Krugers Halimoen Film Cino Motion Film Halimoen Film Halimoen Film Cinowerk Carli Tan’s Film Krugers Film-Bedrijf Krugers Film-Bedrijf M.H. Schilling Halimoen Film 1929 1930 1931 1932 Sumber : HM Johan Tjasmadi, 100 Tahun Bioskop di Indonesia (1900-2000), Megindo, Jakarta, 2008. 364 Victor C. Mambor, Loc.Cit. 438 Pada periode berikutnya yakni periode 1933 – 1936 industri perfilman lokal juga memperlihatkan angka yang cukup menggembirakan seperti yang terlihat pada matrik di bawah ini. Matrik 41 Film Produksi 1933-1936 Tahun 1933 1934 1935 1936 Judul Film Delapan Djago Pedang Delapan Wanita Tjantik Doea Siloeman Oeler Ang Hai Djie Pareh Tie Pat Kai Kawin Poei Sie Giok Pa Loei Tay Anak Siloeman Oeler Poeti Lima Siloeman Tikoes Pembakaran Bio Sutradara The Teng Chun The Teng Chun Pendukung Cino Motion Pictures Cino Motion Pictures The Teng Chun The Teng Chun Albert Balink The Teng Chun Tidak tercatat Cino Motion Pictures Java Industrial Film Java Pacific Film Java Industrial Film Yo Kim Tjan The Teng Chun Jaya Industrial Film The Teng Chun The Teng Chun Jaya Industrial Film Jaya Industrial Film Sumber : HM Johan Tjasmadi, 100 Tahun Bioskop di Indonesia (1900-2000), Megindo, Jakarta, 2008. Mulai tahun 1937 hingga masuknya penjajahan Jepang, industri perfilman lokal semakin tumbuh dengan baik. Dalam kurun waktu 5 tahun yakni selama periode 1937-1942 produksi film lokal memperlihatkan pertumbuhan yang cukup menggembiran seperti tergambar pada matrik berikut ini. Matrik 42 Film Produksi Tahun 1937-1942 Tahun 1937 1938 1940 Judul Film Gadis yang Terdjoeal Terang Boelan Fatima Oh lhoe Tjiandjoer Alang-alang Gagak hitam Impian di Bali Resia si Pengkor Siti Akbari Bajar Dengan Djiwa Dasima Sutradara The Teng Chun Albert Balink Joshua Wong The Teng Chun The Teng Chun The Teng Chun Joshua Wong Tidak tercatat The Teng Chun Joshua Wong R. Hu The Teng Tjun Pendukung Java Industrial Film ANF Tan’s Film Java Industrial Film Java Industrial Film Java Industrial Film Tan’s Film Djawa Film Java Industrial Film Tan’s Film Djawa Film Java Industrial Film 439 Harta Berdarah Kartinah Kedok Tertawa Kris Mataram 1940 Matjan Berbisik Melati van Agam Pah Wongso Pendekar Boediman Rentjong Atjech Roekihati Sorga Ka Toejoe Sorga Palsoe Zoebaedah 1941 Air Mata Iboe 1941 Ayah Berdosa Aladin Dengan Lampoe Wasiat Asmara Moerni Boedjoekan Iblis Djantoeng Hati Elang Darat Garoeda Mas Ikan Doejoeng Koeda Sembrani Lintah Darat Matula Mega Mendoeng Moestika Dari Djenar Noesa Panida Pah Wongso Tersangka Panggilan Darah Pantjawarna Poestaka Terpendam Poetri Rimba Ratna Moetoe Manikam (Djoela Djoeli Bintang 3) Selendang Delima Si Gomar Singa Laoet Siti Noerbaja Soeara Berbisa Srigala Item R. Hu Andjar Asmara Jo An Djan Njoo Cheong Seng Tan Tjoei Hock Tan Tjoei Hock Tidak tercatat Union Film Co New Industrial Film Union Film Co Oriental Film Coy The Teng Chun Joshua Wong Joshua Wong The Teng Tjoen Njoe Cheong Seng Njoe Cheong Seng Wu Tzun Wong Bersaudara Java Industrial Film Tan’s Film Tan’s Film Java Industrial Film Oriental Film Coy Rd. Arifien Jo An Dijien Njoo Cheong Seng Inoe Perbatasari Jo An Djan Lie Tek Swie Wong Bersaudara Wu Tzu Tan Tjoei Hock Boen Kim Nam Jo An Djan Anjar Asmara Union Film Coy Populer Film Coy Majestic Film Coy Wu Tzun Suska Njoo Cheong Seng Tidak tercatat Inoe Perbatasari Suska Henry L. Duarte Tan Tjoei Hock Tan Tjoei Hock Lie Tek Swie Wu Tzun Tan Tjoei Hock Java Industrial Film Java Industrial Film Star Film Majestic Film Coy Star Film Tan’s Film Jacatra Picture Populer Film Coy Standard Film Tan’s Film Star Film Action Film Union Film Coy Populer Film New Java Industrial Film Star Film Oriental Film Oriental Film Tan’s Film Jacatra Film Coy New Java Industrial Film Standard Film Action Film Action Film Standard Film Star Film Action Film 440 Tengkorak Hidoep Tjioengwanara Wanita Satria Boenga Sembodja Poelo Inten 1001 Malam 1942 Tan Tjoei Hock Yo Eng Sek Rd. Arifien Moh. Said HJ Tidak tercatat Wu Tzun Action Film Star Film Union Film Populer Film Coy Populer Film Coy Star Film Sumber : HM Johan Tjasmadi, 100 Tahun Bioskop di Indonesia (1900-2000), Megindo, Jakarta, 2008. Sejak masuknya penjajahan Jepang pada tahun 1942 – 1944 produksi film lokal mulai memperlihatkan penurunannya secara kuantitatif seperti tergambar pada matrik di bawah ini. Matrik 43 Film Produksi Tahun 1942-1944 Tahun 1943 Judul Film Berjoang Di desa Di menara 1944 Djatoeh berkait Gelombang Hoedjan Keris Poesaka Keseberang Sutradara Raden Arifin Rustam St Panindih Rustam St Panindih B. Koesoema Tidak tercatat Inoe Perbatasari Tidak tercatat Raden Arifin Pendukung Nippon Eiga Sha Nippon Eiga Sha Nippon Eiga Sha Nippon Eiga Sha Nippon Eiga Sha Nippon Eiga Sha Nippon Eiga Sha Nippon Eiga Sha Sumber : HM Johan Tjasmadi, 100 Tahun Bioskop di Indonesia (1900-2000), Megindo, Jakarta, 2008. Pasca Kemerdekaan industri perfilman nasional mulai berbenah kembali dan tumbuh sangat lamban. Usaha pembangunan perfilman tersebut misalnya dengan kembali mengimpor film-film asing, pendirian perusahaan Film Nasional Indonesia (Parfini) dan Perseroan Artis Republik Indonesia, lahirnya Festival Film Indonesia dan sebagainya, tetapi usaha-usaha itu belum cukup menggairahkan produksi film lokal. 365 Baru pada tahun 1970, industri film menunjukkan gairahnya kembali. Dalam kurun waktu 1970-1980 terjadi tingkat produksi tertinggi 366 yakni pada tahun 1977, alasannya tak lain karena peraturan pemerintah yang mengharuskan para importer film untuk memproduksi 365 366 Ibid. Ibid. 441 film lokal. 367 Selanjutnya di era tahun 80-an produksi film nasional semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penonton dan bioskop baik di kota-kota besar, daerah-daerah pinggiran kota. Bioskop-bioskop tersebut telah mengakibatkan tersegmentasinya kelas tontonan dan penontonnya. 368 Namun demikian, keadaan ini selama beberapa tahun justru menjadikan perhatian bioskop-bioskop besar kepada film-film Hollywood yang lebih menjanjikan profit, sedangkan film lokal dengan tema semakin monoton, mulai tergeser peredarannya di bioskop-bioskop kecil dan pinggiran, itupun masih harus bersaing dengan film-film India yang sejak awal menjadi konsumsi pasar kelas menengah ke bawah, apalagi di akhir era 80-an minat kondisi film nasional semakin parah dengan hadirnya stasion televisi swasta yang menyajikan film-film impor, sinema elektronik dan telenovela. 369 Pada dekade 90-an kondisi film Indonesia belum juga bangkit dari keterpurukannya. 370 Dalam masa ini harus diakui terdapat beberapa film yang dianggap berkualitas dan sukses bersaing dengan film-film impor seperti ”cinta dalam sepotong roti”, ”daun di atas bantal” yang disutradarai oleh Garin Nugroho, namun demikian kesuksesan tersebut tidak diikuti dengan lahirnya kreativitas film berkualitas dari sineas lainnya sehingga industeri perfilman nasional mengalami kemunduran. Keadaan tersebut diperberat lagi dengan kekalahan film-film nasional dalam menghadapi persaingan dengan film-film asing yang ditayangkan melalui televisi swasta dan televisi kabel 371 Puncaknya semakin diperburuk oleh suatu keadaan, ketika masyarakat yang mulai mengenal teknologi digital lebih senang menikmati film-film impor melalui teknologi laser disc, VCD, namun terdapat terdapat juga sisi baik dari hadirnya teknologi digital bagi dunia perfilman Indonesia, yakni terbangunnya komunitas film-film independen. 372 Mulai akhir dekade 90-an hingga saat ini, produser-produser film nasional sudah mulai memperlihatkan kegairahannya untuk kembali membangun industri perfilman nasional. Tidak sedikit karya film dalam beberapa tahun terakhir bahkan mendapat minat di hati para konsumen lokal. Namun demikian, hal tersebut oleh banyak kalangan masih disangsikan sebagai kebangkitan perfilman nasional, mengingat 367 Ibid. Ibid. 369 Ibid. 370 Misbach Yusa Bira, Op.Cit, hal. 60. 371 Victor C. Mambor, Loc.Cit. 372 Ibid. 368 442 dalam catatan sejarah film Indonesia dari waktu ke waktu terus timbul dan tenggelam. Sektor industri hiburan konvensional (mekanik sinematografi) mulai digantikan peranannya oleh industri hiburan modern (elektronik videografi). Disusul oleh krisis moneter yang mulai terasa pada tahun 1996 berlanjut menjadi krisis moneter dan ekonomi pada tahun 1998 merupakan pukulan terakhir yang membuat perekonomian Indonesia porak-poranda yang dampaknya secara langsung terasa benar oleh dunia perfilman di Indonesia, dimana produksi film tersebut merosot. Namun pada 10 tahun terakhir, produksi film tersebut telah menunjukkan peningkatan sebagaimana terlihat pada matrik di bawah. Matrik 44 Data Statistik Produksi Film Indonesia 2002 – 2012 No Tahun Jumlah Produksi Film 1. 2002 9 2. 2003 4 3. 2005-2006 23 4. 2005 5. 2006 6. 2007 53 7. 2008 75 8. 2009 9. 2010 100 10. 2011 102 11. 2012 90 Sumber : diolah dari berbagai sumber, OK. Saidin, 2013. Matrik di atas menunjukkan bahawa dalam kurun 10 tahun terakhir industri perfilman nasional tumbuh secara fluktuatif dalam arti tidak konstan. Jika pada tahun 2002, industri film nasional hanya mampu memproduksi 9 judul film, tapi kemudian pada tahun 2003, turun menjadi 4 judul film, artinya terjadi penurunan lebih dari 55%. Akan tetapi dalam priode 2 tahun berikutnya (priode 2004-2005), industri film nasional mampu memproduksi 23 judul film atau mengalami pertumbuhan rata-rata 105 %, pada tahun 2004, jika ditarik angka rata-rata 12 judul film untuk tiap tahunnya selama kurun waktu priode 2004-2005. Pada tahun-tahun berikutnya, setelah tahun 2005 angka produksi industri perfilman nasional mulai bergerak menunjukkan peningkatan, jika pada priode 3 tahun terakhir yakni tahun 2003 sampai 2005 jumlah produksi industri film nasional tumbuh secara 443 fluktuatif, maka pada tahun-tahuan berikutnya sudah menunjukan angka pertumbuhan yang konstan, yakni 53 judul film diproduksi selama tahun 2007 dan mengalami pertumbuhan sebanyak rata-rata 50 % sepanjang tahun 2008 yakni sebanyak 75 judul film. Akan tetapi data produksi film nasional pada tahun 2009 sangat mengejutkan . Pertumbuhan industeri film nasional mengalami stagnasi yakni tidak ada karya sinematografi dalam bentuk film bioskop yang diproduksi pada tahun itu. Keadaan ini tidak berlangsung lama, sebab pada tahuntahun berikutnya yakni sepanjang tahun 2010 sampai 2012 produksi film nasional kembali bergerak dan tumbuh secara konstan yakni 100 judul film diproduksi tahun tahun 2009 dan 102 judul film diproduksi sepanjang tahun 2011, meskipun selama priode tahun 2012 kembali mengalami penurunan yakni hanya memproduksi sebanyak 90 judul film saja. Angka-angka ini menunjukkan bahwa, industri perfilman nasional, tidak mampu menjadi industri unggulan sebagai industri kreatif jika dibandingkan dengan Amerika dan India. Amerika (holywood) mampu memproduksi film rata-rata 600 -800 judul setiap tahunnya, atau rata-rata 2 judul film untuk tiap hari, sedangkan India rata-rata memproduksi di atas 1000 judul film pertahun atau lebih kurang 3 judul film rata-rata dapat diselesaikan dalam tiap-tiap hari di sepanjang tahun. Sehingga industri perfilman menjadi industri kreatif yang diunggulkan di kedua negara itu. Seperti yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, di pasar lokal Indonesia, film-film Amerika dan India mendominasi pasar kemudian menyusul film Korea. Beberapa faktor penghambat pertumbuhan industri perfilman nasional, sebenarnya tidak terlepas dari iklim penegakan hukum dalam bidang karya sinematografi, di samping semakin menyeruaknya industri film yang ditayangkan di media elektronik (film sinetron), sehingga hal ini menggusur industri film layar lebar (film bioskop). Di tambah lagi kemajuan pada teknologi siaran yang menyebabkan filmfilm yang selama ini diputar di bioskop sudah dapat masuk ke rumahrumah melalui jaringan TV kabel. Dampaknya kemudian banyak studio-studio atau panggung-panggung bioskop yang dahulu dikenal sebagai PHR (panggung hiburan rakyat) di pedesaan atau studio film di kota-kota besar yang ditutup. PHR nyaris tak terdengar lagi dalam kosa kata perfilman nasional. Jika di kota-kota besar, karya sinematografi masuk ker rumah-rumah penduduk melalui TV kabel, maka di rumahrumah penduduk di pedesaan, karya sinematografi masuk ke rumah melalui VCD dan DVD. Kondisi yang demikian didukung dengan 444 iklim penegakan hukum yang sangat tidak memihak pada kepentingan pemegang hak cipta. Kepingan VCD dan DVD illegal yang dijual dengan harga rata-rata Rp. 3.000,- perkeping pada akhirnya membunuh kreativitas pencipta yang pada gilirannya berpengaruh pada produksi film nasional. Rata-rata biaya produksi untuk satu unit film layar lebar, mencapai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan kadang-kadang investasi sebesar itu tidak dapat dikembalikan dalam waktu yang singkat. Film terakhir yang diproduksi yang termasuk dalam kategori Box Office adalah film Habibie & Ainun yang diproduksi dengan biaya sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) dan penghasilan selama 1 bulan lebih masa penayangannya, di bioskop-bioskop di Indonesia jumlah penonton film Habibie & Ainun mencapai 4.200.000 penonton atau sebanyak Rp. 29.400.000.000. Akan tetapi penghasilan ini tidak dapat berlanjut seperti investasi di sektor perkebunan atau investasi pada sektor industri manufactor lainnya misalnya, yang dapat memberi keuntungan di sepanjang tahun, sebab segera film tersebut di putar di bioskop beberapa hari kemudian kepingan VCD dan DVD illegal beredar di pasaran. Itulah faktor kendala terbesar dalam mendongkrak pertumbuhan industri perfilman nasional. Akibatnya, para produser setingkat Ram Punjabi misalnya, harus memilih investasi di sektor film sinetron yang dibuat dalam cerita bersambung, dan ini praktis mengurangi animo para pembajak, sebab film itu dirancang dibuat secara bersambung dibuat dalam ratusan bahkan ribuan episode berjilid-jilid. Sebut saja Sinetron dengan judul Cinta Fitri yang sudah menghiasi layar kaca hampir 3 tahun, demikian juga sinetron dengan judul “Tukang Bubur Naik Haji” sudah memasuki tahun ke 2 dalam kancah hiburan layar kaca. Pilihan untuk film-film bioskop menjadi tidak menarik lagi secara bisnis. Hitungan-hitungan keuntungannya sulit diprediksi dan jika pembajakan terus berlangsung, bisa jadi para produser akan mengalami kerugian besar. Akibatnya dunia perfilman nasional tak mengenal lagi sosok aktor seperti Slamet Rahardjo, Christina Hakim, Sofan Sofian, Widya Wati, Benyamin S, Rano Karno, Dedi Mizwar yang pada zamannya meraih “Citra” yakni penghargaan tertinggi di dunia perfilman nasional. Sosok sutradara seperti Wim Umboh, Chairul Umam dan Teguh Karya-pun sudah sulit untuk ditemukan pada masamasa sekarang ini. Bahkan tidak jarang kemudian para aktor yang berjaya pada zamannya, justru beralih profesi sebagai politisi, sebut saja, Rano 445 Karno, Dede Yusuf, Sopan Sofyan dan Nurul Arifin, terakhir Dedy Mizwar. Belum lagi sejumlah artis film komedi seperti Miing, Komar dan Eko Patrio, semua mereka terjun ramai-ramai ke dunia politik, mumpung iklim politik Indonesia masih memerlukan tokoh-tokoh populer yang dikenal masyarakat sebagai dampak arus demokrasi liberal yang kerannya baru terbuka pada priode pemerintahan setelah kejatuhan priode kepemimpinan Orde Baru di bawah Rezim Soeharto. Di sisi lain para artis senior hidup dalam suasana memprihatinkan, sebut saja penyakit yang mendera artis antara lain Aminah Cendrakasih yang telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengabdi kepada dunia perfilman nasional akan tetapi pilihannya itu bukanlah pilihan yang menjanjikan. Keadaan ini jauh berbeda dengan artis-artis Hollywood dan Bollywood, mereka tidak hanya terjamin hari tuanya, tapi lebih dari sekedar itu para artis itu menempati peringkat orang-orang yang berpenghasilan tinggi di negaranya. Sebut saja 10 aktor Hollywood terkaya di dunia (berdasarkan peringkat) yaitu : Leonardo DiCaprio ($77 million), Johnny Depp ( $50 million), Adam Sandler ($40 million), Will Smith ($36 million), Tom Hanks ($35 million), Ben Stiller ($34 million), Robert Downey, Jr. ($31 million), Mark Wahlberg ($28 million), Tim Allen ($22 million) dan Tom Cruise ($22 million). Artis-artis Bollywood dengan bayaran termahal (berdasarkan peringkat), adalah Aamir Khan (75,6 miliar rupiah per film), Shah Rukh Khan (37,8 – 47,3 miliar rupiah per film), Salman Khan (43,5 – 51 miliar rupiah per film), Akhsay Kumar (34-41 miliar rupiah per film) dan Rithik Roshan (28,3 – 37,8 miliar rupiah per film). Untuk peringkat artis Indonesia, saat ini yang terkaya adalah Anjasmara dengan total kekayaan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan itu tidak melampaui dari honor satu judul film yang dibintangi oleh Rithik Roshan. Urutan harta kekayaan 10 artis Indonesia (berdasarkan peringkat) adalah sebagai berikut : Anjasmara (20 milyar), Tukul Arwana (15 milyar), Bunga Citra Lestari( 12,7 milyar), Titi Kamal (10 milyar), Luna Maya (6 milyar), Tora Sudiro (3,66 milyar), Dian Sastro Wardoyo (3,24 milyar), Nicholas Saputra (2,5 milyar), Evan Sanders (2,25 milyar) dan Julia Estelle (1,65 milyar). 373 Dalam skala internasional selain India menempati peringkat pertama dalam industri perfilman, ternyata Amerika menempati peringkat kedua sebagaimana tertera pada grafik di bawah ini. 373 2013. http://www.google.com/artis_terkaya_2013, diakses tanggal 2 Agustus 446 Grafik : 4 Produksi Film Dunia Tahun 2012 1288 694 475 448 253 102 84 1 2 126 46 3 Catatan : 1. Republik Indonesia 2. Brazil 3. Australia 4. Amerika Serikat 5. China 6. Jepang 7. Rusia 8. Inggris 9. India Sumber : PBB, Unesco, 2012 4 5 6 7 8 9 447 Indonesia hanya menempati peringkat ke-7 dari 9 negara dalam produksi industri perfilman di dunia. Sinematografi menjadi industri andalan di Amerika. Sebagai industri kreatif, industri perfilman di Amerika menempati peringkat ke dua setelah industri persenjataan pada saat ini. Dengan peringkat yang demikian, maka industri perfilman di Amerika menjadi sebuah industri tempat bergantung sebahagian rakyat Amerika karena industri perfilman Amerika tidak hanya dalam bentuk movie box office akan tetapi juga dalam bentuk home video, basic cable dan pay cable dan industri ini mengalami pertumbuhan yang cukup baik walaupun pada 30 tahun sebelumnya industri perfilman Amerika menempati urutan keempat sebagai penyumbang pendapatan domestic bruto Amerika seperti terlihat pada tabel di bawah ini. Tabel 8 Peringkat Industri Film Amerika Dalam Memberikan Sumbangan Pendapatan Domestik Dibandingkan dengan Industri Yang Lain Sektor industri Industri kedirgantaraan Industri kimia Elektronik dan komputer Industri film Sumber : Pendapatan domestik bruto (US) 134.000.000.000 300.000.000.000 287.000.000.000 480.000.000 Janet Wasko, Hollywood in the Information Age, University of Texas Press, UK, 1995, hal. 2 Akan tetapi, setelah 30 tahun justru industri perfilman Amerika mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Data yang dikemukakan oleh Janet Wasko, yang mengacu pada survei Standard & Poor Industry pada kurun waktu 1986-1991 sumbangan industri perfilman Amerika ke dalam pendapatan domestik negaranya mengalami pertumbuhan 7,9% seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 448 Tabel 9 Domestic filmed entertainment revenues, 1986 and 1991 Revenues 1986 1991 Annual growth rate (%) Consumer spending Moving box office Home video Basic cable Pay cable Consumer total 3,778 5,015 5,225 3,325 17,343 4,803 10,995 11,080 4,715 31,593 4.9 17.0 16.2 7.2 12.7 Advertising Broadcast TV networks TV stations Barter Subtotal National cable Local cable Subtotal Advertising total 8,342 13,085 600 22,027 676 179 855 22,882 9,435 14,675 1,275 25,385 1,530 455 1,985 27,370 2.5 2.3 16.3 2.9 17.7 20.5 18.3 3.6 40,225 58,963 7.9 Total spending Source : Veronis, Suhler & Associates, Motion Picture Association of Amerika, McCann-Erickson, Wilkofsky Gruen Asociates. From : Standard & Poor’s Industry Surveys, 11 March 1993, p. L17 Dengan demikian, jika dalam kurun waktu 1980-an sampai saat ini Amerika secara gencar memerangi pembajakan karya cipta sinematografi asal negaranya, dapat lah dimaklumi, karena sektor industri perfilman Amerika telah menjadi penyumbang dalam pendapatan domestik negaranya. Tidaklah berlebihan jika kemudian Amerika juga menerapkan sanksi-sanksi ekonomi terhadap negara- 449 negara ”pembangkang” yang tidak patuh dengan penegakan hukum hak cipta khususnya hak kekayaan intelektual pada umumnya. 374 Penghargaan-penghargaan yang sifatnya permanen tak pernah diberikan kepada mereka yang menghabiskan waktunya sebagai pekerja seni dalam dunia sinematografi. Itu sangat berbeda jika kita rujuk negara tetangga Malaysia misalnya, aktor setingkat P. Ramlie diberi gelar tertinggi sebagai seniman kerajaan dengan gelar Tan Sri. Bahkan saat ini rumah kediaman beliau dijadikan sebagai museum seni yang merupakan bahagian dari museum kerajaan. Agaknya Indonesia harus bersabar menunggu iklim pemerintahan (birokrasi) dan iklim penegakan hukum yang memberi penghargaan dan perlindungan yang lebih baik pada hasil-hasil karya sinematografi. Jika pada masa pemerintahan Orde Lama, industri perfilman tidak tumbuh lebih dikarenakan suasana politik dan ekonomi bangsa yang belum menempatkan media hiburan sebagai kebutuhan, maka pada masa pemerintahan Orde Baru industri perfilman Indonesia tidak tumbuh dipengaruhi oleh faktor politik. Pada masa itu kreativitas tidak tumbuh dengan baik, karena iklim politik yang menjadikan produksi film nasional yang berkualitas sulit dihasilkan, karena adanya Badan Sensor Film yang mengebiri kreativitas, jika jalan cerita film itu menampilkan kritik terhadap rezim pemerintah yang berkuasa pada waktu itu. Film yang diangkat dari peradaban budaya bangsa antara lain yang bertemakan kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat tidak mendapat tempat dalam industeri film nasional sehingga pada tahun-tahun itu industri film nasional lebih banyak banyak memproduksi film cerita yang menampilkan eksploitasi dan eksplorasi seksual. Artis-artis yang berani beradegan “panas” sebut saja Yatty Octavia, Nurul Arifin, Yurike dan Inneke Kusherawaty adalah namanama artis yang diberi julukan Bom Sex. Hampir semua film-film yang mereka bintangi merupakan film-film cerita yang berkualitas rendah dan jauh dari pesan-pesan moral, etika apalagi diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi kemajuan peradaban bangsa. Meskipun pada waktu itu lahir juga film-film yang berkualitas yang dibintangi oleh Cristine Hakim seperti Tjut Nya’ Dien dan Yenny Rahman dengan judul film Gadis Meraton”, namun intensitas produksinya tidak 374 Seperti pada paruh awal tahun 1980-an, penolakan eksport garmen Indonesia karena banyaknya pelanggaran terhadap karya cipta warga negara Indonesia yang dibajak di Indonesia yang berujung pada perubahan Undang-undang Hak Cipta Indonesia tahun 1982 ke Undang-undang hak Cipta No.7 Tahun 1987. Lihat lebih lanjut OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. 450 sebanding dengan film-film yang bertemakan eksplorasi seksual dan sensual. Saat ini iklim keterbukaan menjanjikan tumbuhnya kreativitas, akan tetapi kendala berikutnya, adalah film-film cerita yang berkualitas selalu menghabiskan biaya produksi yang besar, di sisi lain perlindungan hukum terlalu lemah untuk melindungi hak-hak mereka. Alhasil industri perfilman nasional bak kata pepatah “seperti kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau”. F. Gagasan Ideal Pilihan Politik Hukum ke Depan Tulisan ini harus diakhiri dengan sebuah gagasan hukum Indonesia masa depan. Sebuah hukum yang konsisten dalam melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta menciptakan perdamaian dunia yang abadi. Bukan hukum yang melulu melindungi kepentingan asing, hukum yang hanya mampu menyejahterakan segelintir orang dan menciptakan semakin banyak rakyat miskin atau hukum yang menimbulkan kesenjangan sosial, hukum yang mewujudkan semakin hari semakin banyak rakyat terjerumus dalam kepicikan, kebodohan, kehilangan kecerdasan intellektual dan kehilangan kecerdasan nurani serta hukum yang membuka eksploitasi sebesar-besarnya terhadap kekayaan alam yang kemudian dinikmati oleh negara industeri maju yang berujung pada kesenjangan ekonomi di berbagai belahan dunia yang memicu peperangan. Pilihan politik hukum transplantasi sebenarnya bukanlah pilihan politik hukum yang salah. Hampir sebagian besar hukum perdata (code civil) negara-negara penganut eropa continental hukum yang terbentuk di negaranya hari ini adalah hasil transplantasi hukum yang berasal dari Code Civil Prancis atau Napoleon Code. Code Civil sendiri berasal dari hukum Romawi dan hukum Romawi itu bersumber dari Corpus Juris Civil dari Kaisar Justian pada masa dinasti Byzantium (Kekaisaran Romawi). Dalam tulisannya berjudul The Evolution of Western Private Law (2001), Watson mengatakan bahwa hukum perdata Eropa berevolusi dari Corpus Juris Sipilis yang berpangkal pada konstitusi atau Codex Justinian yang diprakarsai oleh Kaisar Justinian pada tanggal 13 Februari 528. Watson 375 menulis : 451 Justinian became coemporer of the Byzantine Empire with his uncle Justin in 527. Later that year, when his uncle died, he became sole emporer. Probably even while Justin had been sole ruler, Justinian was contemplating a legal codification of same kind. He issued a constitution dated 13 February 528, establishing a commission to prepare a new collection, a Codex, of imperial constitutions. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Justian untuk membentuk sebuah komisi untuk menyelesaikan codex yang kemudian diterbitkan pada tanggal 7 April 528. Codex yang disusun terakhir ini belum begitu sempurna sehingga harus ditata kembali dalam bentuk kampulan teks dan berhasil dirumuskan pada tanggal 15 Desember 530. Kumpulan teks hukum itu dijadikan bahan pelajaran untuk mahasiswa tahun-tahun pertama di Institut Gayus, yakni sebuah istitut yang mengajarkan hukum atau ilmu perundang-undangan. Pada institute itu juga sedang didalami codex yang bersumber dari hukum Kristiani pada tahun 160. Akhinya tersusunlah codex dalam 50 buku pada tanggal 30 Desember 533, seperti yang diungkapkan oleh Watson. 376 The Code, which was published on 7 April 528, has not survived, but it was replaced by a second revised code, which came into effect on 29 December 534. The revised code, which has survived and is one of the four constituent elements of what came to be called the Corpus Juris Civilis, is divided into twelve books, subdivided into titles in which the constitutions appear chronologically. The constitutions range in date from Hadrian in the early second century to Justinian himself. A considerable proportion of the texts – 2, 019 as against 2,664 - come from the time after the empire became Christian ; in fact, the bulk of the Christian rescripts is much greater. On 15 December 530, Justinian ordered the compilation of a collection of juristic texts, the Digest, and the work came into force on 30 December 533. This massive work, twice the size of the Code, is in fifty books, virtually all of which are subdivided into titles. Dengan politik tambal sulam, akhirnya pada tanggal 7 April 528, codex itu dipublikasikan dan pada tanggal 29 Desember 534 tersusunlah sebuah kodifikasi hukum perdata yang disebut kodifikasi justianus yang dikenal juga sebagai kodifikasi hukum Romawi yang dikemudian hari disebut sebagai Corpus Juris Civilis. Sampai saat ini codex itu masih ada dan tersimpan di Yunani dalam bahasa Yunani dan bahasa Latin. Corpus Juris Civilis ini kemudian menjadi model atau contoh pembentukan hukum perdata di sebahagian besar Benua Eropa, terutama setelah Perancis di bawah penaklukan Napoleon Bonaparte 375 Lihat lebih lanjut Alan Watson, The Evolution of Western Private Law, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 2001, hal 2. 376 Ibid. 452 menebar benih-benih hukum Romawi ini ke seluruh wilayah taklukannya. Negara pertama yang ditaklukkan oleh Napoleon adalah Belgia pada tahun 1797 dan diberlakukanlah Code Civil Perancis pada tahun 1804. Belanda yang letaknya bersebelahan dengan Belgia pada waktu itu bersikap netral, akan tetapi pada tahun 1806 Napoleon memaksa Belanda untuk menerima Code Civil Perancis meskipun pada waktu itu keberlakuannya tetap memperhitungkan praktek hukum Belanda yang telah berlangsung sebelumnya. Pada tahun 1810 Napoleon menganeksasi Belanda dan diterapkanlah Code Civil Perancis di wilayah itu. Akan tetapi setelah Napoleon jatuh, Belgia dan Belanda bersatu dan di wilayah tersebut tetap berlaku Code Civil Perancis. Tahun 1830 Belgia dan Belanda memisahkan diri, Belanda membentuk sebuah komisi negara yang bertugas untuk menyusun undang-undang dan tersusunlah Code Civil yang disebut Burgerlijk Wetboek, dan mulai berlaku tahun 1838, seperti yang ditulis oleh Watson. 377 The first steps in the reception of the French Code civil were the direct result of Napoleon’s conquests. Belgium was incorporated into France in 1797, and the Code civil automatically came into force in 1804, and remained in force despite Napoleon’s fall. The Natherlands, despite its neutrality, was forced more and more into the French sphere of influence, and in 1806 Napoleon compelled them to accept a version of the Code civil that was slightly altered to take account of some Dutch legal practices. In 1810 Napoleon annexed the Netherlands, and the original Code civil was introduced. After Napoleon’s fall, Belgium and the Netherlands were united. The Code civil was to remain in force until a fresh code could be issued, but Belgium separated in 1830, and a new Dutch commissions was appointed, whose proposed code, the Burgerlijk Wetboek, came into force in 1838. Ada yang menarik dari transplantasi Code Civil Perancis ke dalam KUH Perdata Belanda, yakni sekalipun Perancis tidak lagi memiliki kekuasaan di wilayah Belanda karena kekalahan Napoleon, akan tetapi Belanda tetap memberlakukan Code Civil Perancis itu. Bahkan pada tahun 1947 Belanda merevisi Code Civilnya akan tetapi tidak meninggalkan Original Basic (basis asli) dalam praktek pembentukan undang-undangnya yang baru itu. Code Civil Perancis tetap dijadikan sebagai model dan secara substantif materi yang diatur dalam Kitab Undang-undangnya masih sebahagian besar bersumber dari Code Civil Perancis tersebut hanya pada bahagian-bahagian tertentu yang disempurnakan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman pada waktu itu. Hingga akhirnya didalam Kitab Undang-undang 377 Ibid, hal. 223. 453 tersebut telah dimasukkan pula tentang hukum dagang yang juga bersumber dari Code Commerce Perancis. 378 Di kemudian hari Burgerlijk Wetboek Belanda itu berdasarkan asas konkordansi diberlakukan di wilayah Hindia Belanda melalui Staatsblaad No. 23 Tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesie dan dinyatakan berlaku pada tahun 1848 bersamaan dengan diberlakukannya Wetboek Van Koophandel pada tanggal 1 Mei 1848. Sama seperti Belanda yang hukumnya ditransplantasi dari hukum Perancis, dan hukum itu dapat diberlakukan dan diterima oleh masyarakat Belanda, maka di Indonesia hukum perdata dan hukum dagangnya di transplantasi dari hukum Belanda. Akan tetapi perbedaannya hukum perdata Belanda tidak semuanya dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak atas tanah misalnya harus dikeluarkan dari Buku ke II KUH Perdata karena dipandang tidak sesuai dengan “cita rasa” masyarakat Indonesia, untuk selanjutnya dalam rangka menyahuti kebutuhan hukum nasional yang bercorak Indonesia, diterbitkanlah Undang-undang No. 5 Tahun 1960. Demikian juga ketentuan mengenai perkawinan harus dikeluarkan dari Buku I KUH Perdata untuk selanjutnya Indonesia membuat undang-undang tentang perkawinan yang bercorak Indonesia yang dituangkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Ketentuanketentuan lain yang juga dikeluarkan dari wet yang bersumber dari pemerintah Kolonial Belanda secara evolusi terus dilakukan. Hukum tentang perusahaan misalnya, telah dikeluarkan dari Kitab Undangundang Hukum Dagang yang sesungguhnya bersumber dari Wetboek van Koophandel yang berakar pada tradisi Code de Commerce Perancis yang berpangkal pada Corpus Juris Civilis buatan Kaisar Justinian yang disusun secara sistematis pada masa Kekaisaran Romawi. Peristiwa-peristiwa sejarah di atas, telah cukup memberi gambaran bahwa proses transplantasi hukum telah berjalan selama berabad-abad di dunia dan itu adalah sebuah proses peradaban (kebudayaan). Dalam konteks ini, hukum tidak lagi semata-mata dilihat sebagai gejala normatif akan tetapi hukum adalah gejala sosial. Perubahan sosial dalam masyarakat adalah sebuah keharusan yang tidak dapat ditolak, sejalan dengan itu perubahan peradabanpun akan 378 Di Belanda, Kitab Undang-undang Hukum Dagang disusun pada tahun 1838 Code Civil dan Code de Commerce dinyatakan berlaku di negeri Belanda, Burgerlijk Wetboek diadopsi dari Code Civil Perancis, Wetboek Van Koophandel diadopsi dari Code de Commerce. Wetboek Van Koophandel ini kemudian diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1838 dan berdasarkan asas konkordansi WvK ini diberlakukan di Indonesia pada tanggal 1 Mei 1848. 454 berjalan secara simetris yang didalamnya mau tidak mau perubahan hukum (legal change) akan ikut terbawa karena hukum meresap ke setiap sel kehidupan sosial sebagaimana diungkapkan oleh Gary Slapper & David Kelly ketika menulis sistem hukum Inggris. Slapper dan Kelly mengungkapkan 379 : Law permeates into every cell of social life. It governs everything from the embryo to exhumation. It governs the air we breathe, the food and drink that we consume, our travel, sexuality, family relationships, our property, the world of sport, science, employment, business, education, health, everything from neighbor disputes to war. Taken together, the set of institutions, processes, law and personnel that provide the apparatus through which law works, and the matrix of rules that control them, are known as the legal system. This system has evolved over a long time. Today it contains elements that are very old, such as the coroner’s courts, which have an 800 year history, and elements that are very new, such as electronic law reports and judges using laptops. A good comprehension of the English legal system requires knowledge and skill in a number of disciplines. The system itself is the result of developments in law, economy, politics, sociological change and the theories that feed all these bodies of knowledge. This book aims to assist students of the English legal system in the achievement of a good understanding of the law and its institutions and processes. We aim to set the legal system in a social context, and to present a range of relevant critical views. 379 Lebih lanjut lihat Gary Slapper & David Kelly, The English Legal System, Routgedge, Belanda, 2011, hal. ix. 455 456 Di kemudian hari Code Civil dan code commers Prancis yang berasal dari hukum Romawi (Justinian Code, Corpus Juris Civilis) berlangsung di berbagai belahan dunia. Di Spanyol demikian tulis Watson dibuat hukum dagang yang berbasis pada Napeleon’s Code pada tahun 1829, kemudian dibuat versi modern pada tahun 1885. Kemudian pada tahun 1889 dibuat hukum perdata yang disebut dengan The Spanish Codigo Civil. Portugal juga mengadopsi hukum dagang Prancis pada tahun 1833 kemudian diperbaharui pada tahun 1888 demikian dalam lapangan hukum perdata portugal mengadopsi hukum Prancis dan dimuat dalam Portuguise Civil Code pada tahun 1867. Khusus untuk negara-negara Afrika sub sahara, perjalanan transplantasi hukum Perancis persis sama dengan Indonesia. Prancis menjajah negara-negara itu yang sesungguhnya dalam negara itu sdudah ada hukum kebiasaan dan hukum Islama. Akan tetapi setelah kolonial Perancis berakhri, negara-negara itu kemudian memodifikasi hukumnya dengan melihat model hukum Prancis. Itu terjadi di Algeria (1834), Tunisia (1906) dan Maroko (1913) kemudian menyebar dan membawa pengaruh ke negara Egipt dan Lebanon. Di Amerika Utara tepatnya di negara bagian Louisiana ketika Prancis menyerahkan wilayah itu kepada United State pada tahun 1803, juga mengadopsi hukum perdata Prancis dan itu terjadi pada tahun 1808, pada waktu hukum dagang tidak ikut di adopsi, baru kemudian itu terjadi pada tahun 1825 dan dilanjutkan pada tahun 1870.380 Untuk kasus Indonesia, sebenarnya apa yang sudah berlangsung pada masa Hindia Belanda tidak terlalu buruk untuk diteruskan pada hari ini, asal saja transplantasi itu benar-benar dilakukan setelah memasukkan unsur Ke-Indonesiaan, atau hukum yang berkepribadian bangsa. Hukum dengan jati diri bangsa yakni hukum yang bersumber dari landasan ideologi Pancasila. Indonesia ke depan harus mampu melahirkan undang-undang nasional yang konsisten dengan nilai-nilai kultural masyarakatnya, nilai-nilai yang disebutkan sebagai nilai-nilai dengan paradigma budaya dan sosial Indon esia yang asli (The original paradigmatic values of Indonesian culture and society) yang terabstraksi dalam Pancasila. Pancasila yang telah terima sebagai landasan ideologi bangsa dan negara haruslah ditegakkan meminjam istilah orde baru secara murni dan konsekuen. Muri bermakna original, tidak bercampur baur antara yang haq (benar) dengan yang bathil (salah). Konsekuen berarti 380 Ibid, hal. 225-226. 457 bertanggung jawab dengan kesungguhan hati nurani, tidak munafik (hipokrit) dan tidakk pula larut dalam hayalan (apologi). Harus diakui bahwa, belajar dari pengalaman politik transplantasi hukum asing ke dalam undang-undang hak cipta nasional, banyak peristiwa yang dapat direkam. Selama kurun waktu satu abad pemberlakuan undang-undang hak cipta di negeri ini mulai zaman kolonial hingga era globalisasi, semangat untuk melindungi karya cipta anak bangsa, semangat untuk menumbuhkan kreativitas penciptaan yang memihak pada faham kebangsaan atau kepentingan bangsa, kelihatannya kandas di tangan anak bangsa sendiri. Penyebabnya sepanjang yang dapat dicerna antara lain adalah : 1. Sejak masa kolonial belanda bangsa ini terjebak dalam arus pikir kapitalis dan liberal, hukum adat yang semula telah diperjuangkan oleh Van Vollenhoven dan Ter Haar dapat dijadikan cikal bakal pembentukan hukum nasional, justeru tak berhasil diperjuangkan atau diteruskan pada masa setelah negeri ini merdeka. Kaum bumi putera justeru bangga bila suatu waktu pada zaman Kolonial ia dapat menundukkan diri pada hukum Eropa, atau oleh pemerintah kolonial dipersamakan dengan golongan Eropa dengan politik hukum, pernyataan berlaku, persamaan hak dan tunduk sukarela. Kaum “inlander” yang baru merubah pola makannya dari “getuk” ke “keju” begitu terkesimah dengan konsep kodifikasi dan unifikasi hukum. 2. Pilihan politik hukum pragmatis yang secara terus menrus dilakukan pasca kemerdekaan. Kebijakan legislasi diarahkan pada gerakan kodifikasi parsial dan di pilih sebagai politik hukum nasional baik itu bersumber pada undang-undang peninggalan kolonial (termasuk hak cipta) maupun yang bersumber dari kesadaran hukum masyarakat dan Perjanjian Internasional sebagai konsekuensi dari keberadaan Indonesia dalam pergaulan Internasional. 3. Lemahnya pengelolaan manajemen negara dalam sistem kehidupan nasional yang berpangkal pada ego sektoral, lemahnya kapital, lemahnya SDM dan berujung pada lemahnya posisi tawar (bargaining position) di mata dunia Internasional yang pada gilirannya hilang kemandirian negara dan muncul hukum nasional yang berhubungan dengan kepentingan dunia internasional. Pada tataran basic policy Indonesia tak cukup kuat “menangkis” atau menolak untuk 458 masuknya klausule-kalusule yang melindungi kepentingan asing dalam norma undang-undang Hak Cipta Nasionalnya. Padahal di banyak negara, sebut saja India, Singapura dan Cina mereka sangat selektif untuk memasukkan keinginan asing tersebut, bila bertentangan dengan kepentingan nasional negaranya, dalam kasus penyesuaian peraturan perundangundangan Hak Kekayaan Intelektual negaranya dengan TRIPs Agreement. 4. Tak adanya bekal yang cukup kuat dan tangguh kalangan anggota legislatif yang bekerja di sektor legislasi nasional, kalangan pemerintah yang selama ini banyak mengajukan usulan Rancangan Undang-undang tak juga dibekali dengan hasil-hasil riset akademik, lebih dari itu rekomendasi kalangan perguruan tinggi tak selalu disikapi dengan arif oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyusunan Undang-undang (sekalipun disebut sebagai naskah akademis tapi muatannya lebih pada kepentingan politik praktis yang sangat pragmatis) nasional dan tidak terpola secara sistemik. Pekerjaan legislasi dilakukan secara tambal sulam, bongkar dan rombak seperti modifikasi yang dikenal dalam dunia otomotif. Meski dapat berjalan, tapi selalu terseok-seok ketika menghadapi tikungan tajam, berbukit terjal dan berliku. Ketika terjadi “mogok” bongkar dan direvisi kembali. Itu yang terjadi selam kurun waktu 100 tahun berlakunya UU hak cipta, atau telah terjadi 4 kali revisi sejaka masa kemerdekaan. Cukuplah empat alasan ini untuk membuka wawasan dan wacana diskursus di kalangan akademis, jika negeri yang besar ini ingin dipertahankan dengan segenap simbol dan jati dirinya. Pilihan politik hukum pragmatis yang dipicu oleh pandangan kapitalis dan liberal memang telah melahirkan para politisi “kutu loncat” yang lebih banyak menghabiskan waktunya untuk memikirkan diri sendiri ketimbang kepentingan negaranya. Idealisme para politisi tempat masyarakat menggantungkan harapannya agar dapat melahirkan hukum dan perundang-undangan sesuai hati nurani rakyat tak lagi dapat tertampung. Persoalan pembenahan secara internal, agaknya menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melangkah dalam kancah pertarungan global. Bagaimanapun juga negar-negar maju secara simultan akan akan tetap melancarakan politik ekonomi dan politik keamannya di berbagai belahan dunia yang mengarah pada penaklukan negara-negara berkmbang. Mulai lewat 459 bantuan keuangan berupa pinjaman, bantuan tenaga ahli, bantuan militer sampai pada ekspansi militer jika negara yang bersangkutan dianggap membangkang. Berkali-kali Indonsesia ditempatkan sebagai negara pembajak dengan daftar hitam menurut versi Amerika dan sejalan denganitu berkali-kali pula Indonesia mendapat sanksi ekonomi. Misalnya ketika Indonesia memiliki unggulan eksport seperti tekstil, ancaman Amerika untuk mengembalikan atau menolak ekspor garrmen (produk tekstil) Indonesia akan dijalankan, jika Indonesia tidak segera mengatasi pembajakan karya cipta anak bangsa mereka di Indonesia. Kasus pembajakan lagu-lagu Bob Geldof adalah contoh konkrit bagaimana kemudian Amerika menekan Indonesia untuk merobah UU hak cipta Nasionalnya ketika itu (perubahan UU No. 6 Tahun 1982 menjadi UU No. 7 Tahun 1987). Globalisasi memang telah menjadi sarana negaranegara maju untuk melancarkan “imperialism” model baru. Penjajahan dalam bidang ekonomi, politik dan keamanan dengan bermacam-macam isu yang dikemas, mulai dari isu HAM, isu lingkungan sampai pada isu teroris. The new imperialism demikian kata David Harvey. 381 Penjajahan untuk merebut sumber-sumber ekonomi yang sebahagian besar dimiliki oleh negara-negara berkembang terus berlangsung. Untuk kasus Indonesia saja, penambang emas Freeport dalam sebahagian kecil saja contoh bagaimana the new imperialism itu menjalankan misinya. Tentu saja semua ini tak mengharuskan kesalahan itu dikembalikan kepada pihak investor. Hukum investasi Indonesia tentang PMA yang lebih awal harus dipertanyakan. Apakah peluang eksploitasi yang membuka jalan imperialism gaya baru itu memang telah terbuka lebar dalam ketentuan undang-undang PMA Indonesia. Jika memang begitu, maka pertanyaannya harus dijawab kembali oleh anak bangsa ini. Awak yang tak pandai menari janganlah dikatakan lantai terjungkat, sepatu sempit jangan kaki diraut, begitu kata pepatah Melayu. Peradaban Barat memang tumbuh dari budaya eksploitasi. Falsafah hidup masyarakat Jepang, “ambillah secukupnya dari alam”, hanya dikenal oleh bangsa-bangsa di Asia. Kondisi geografis dengan berbagai perubahan cuaca yang terkadang ekstrim membuat Barat (Eropa) tumbuh dalam budaya “menabung” dan persiapan bekal makanan untuk untuk ”hari esok”. Tradisi ini tak lazim dan tak dikenal pada masyarakat asia pada umunya, karena makanan cukup tersedia 381 Lebih lanjut lihat David Harvey, Imperialisme Baru Genealogi dan Logika Kapitalisme Kontemporer, Resist Book, Yogyakarta, 2010. 460 dari alam setiap waktu. Munculnya keinginan untuk menguasai wilayah yang kaya akan sumber “hari esok” itu pada akhirnya menimbulkan budaya eksploitasi yang diiringi dengan tindakan imperialism. Itu yang terjadi selama bertahun-tahun yang memunculkan Perang Dunia I dan disusul dengan Perang Dunia II. Inti dari peperangan itu adalah kerakusan manusia yang dibungkus dengan nafsu kekuasaan yang berujung pada penguasaan sumber daya alam sebagai cadangan “hari esok” itu. Kekalahan Napoleon menyentakkan kesadaran Barat dan ini adalah awal kegagalan sistem negara Eropa, seperti yang dilkukiskan oleh Marvin Perry 382 : Kegagalan sistem negara Eropa sejajar dengan krisis budaya. Sejumlah intelektual Eropa menyerang tradisi rasional Pencerahan dan merayakan hal yang primitive, naluriah dan nonrasional. Orang muda semakin banyak yang tertarik kepada filsafat tindakan yang menertawakan nilai-nilai berjois liberal dan memandang perang sebagai pengalaman yang memurnikan dan memuliakan. Perang-perang colonial, yang digambarkan dengan bersemangat dalam pers populer, membakar imajinasi para pekerja pabrik yang bosan, lamunan mahasiswa, memperkuat rasa tanggungjawab dan keberanian di kalangan serdadu dan aristocrat. Perang-perang colonial kecil yang “megah” ini membantu membentuk sikap yang membuat perang dapat diterima, jika tidak patut dipuji. Kerinduan untuk lari dari kehidupan mereka sehari-hari dan menganut nilai-nilai hereoik, banyak orang Eropa memandang konflik kekerasan sebagai ungkapan tertinggi kehidupan individu dan nasional. “Jika ada perang, bahkan yang tidak adil sekalipun”, tulis George Heym, seorang penulis muda Jerman pada 1912. “Perdamaian ini begitu busuk”. Meskipun teknologi sedang membuat peperangan lebih brutal dan berbahaya orang Eropa tetap menganut ilusi romantik tentang pertempuran. Peradaban Barat yang penuh dengan kisah peperangan itu memberi warna juga pada pilihan produk industeri mereka seperti industeri senjata perang dan bahkan industri perfilman merekapun didominasi oleh cerita perang. Seiring dengan perang senjata yang masih bergolak di sebagian wilayah Timur Tengah, perang ideologipun terus berlangsung. Kemenangan Amerika dengan ideologi kapitalis 382 Wajah peradaban Barat memang diwarnai oleh peperangan. Sebenarnya tidak hanya Barat, sejarah Asia dan Timur Tengahpun di penuhi dengan peperangan. Ada yang berskala lokal dan ada yang berskala dunia. Sebut saja peperangan di masa kekhalifahan, penaklukan Eropa dan Andalusia oleh Tariq bin Ziad dan Salahuddin Al Ayyubi, dalam perang salib atau perang suci, perang Osmania melawan kerajaan Bizantium, penaklukan Kaisar Jengis Khan, penaklukan Kaisar Cina, penaklukan kerajaan Goa di India sampai dengan perang teluk yang berlangsung sampai hari ini. Di Indonesia sendiri ada juga perang Majapahit dan Sriwijaya. Pendek kata sejarah peradaban umat manusia dipenuhi dengan peperangan. Lebih lanjut lihat Marvin Perry, Peradaban Barat Dari Revolusi Prancis Hingga Zaman Global, Kreasi Wacana, Bantul, 2013, hal. 249. 461 liberalnya melawan ideologi komunis yang diikuti keruntuhan dominasi Uni Soviet, membuat posisi Amerika semakin berada di atas angin merajai pengendalian peradaban dunia. Kini perang itu telah berubah menjadi perang ekonomi dengan ideologinya masing-masing. GATT/WTO adalah sarana yang dipakai oleh Amerika dan sekutunya untuk penaklukan Asia dan negara-negara dunia ketiga. Saingan terbesar Amerika adalah Cina, India dan Turki yang diperkirakan akan mendominasi perekonomian dunia. Cina dan India telah memperlihatkan pembangkangannya dalam menyikapi TRIPs Agreement sebagai hasil capaian Uruguay Round yang melahirkan kesepatan GATT/WTO. Bagi Indonesia pengalaman Cina dan India patut dijadikan bahan kajian untuk pilihan politik hukum ke depan.Untuk mengalahkan dominasi kapitalis, Indonesia harus kembali ke khittah 18 Agustus 1945, Bahagian ini adalah uraian dan analisis terakhir dari disertasi ini. Jika ditelusuri dari awal sampai pada bahagian terakhir naskah penelitian ini. Salah satu kesan yang dapat ditangkap sebagai pilihan politik hukum dalam pembangunan hukum nasional adalah masih banyak pekerjaan dalam tataran basic policy dan anactment policy yang belum selesai dan belum tuntas. Pembangunan hukum masih dilakukan secara sporadis dan pragmatis menurut kebutuhannya dengan cara tambal sulam. Hal ini akan menimbulkan persoalan tersendiri dalam kebijakan politik pembangunan hukum nasional dan berdampak pula terhadap praktek penegakan hukum. Kebijakan politik hukum yang hendak merumuskan hukum seperti apa yang akan dibangun di negeri ini, bagaimana bentuk hukumnya, seberapa jauh keluasan ruang lingkup berlakunya, bagaimana sistem hukum nasional yang dikehendaki kesemua itu dirumuskan dalam suatu naskah sebagai garis politik hukum atau haluan politik hukum nasional. Di Indonesia hal semacam itu sebelum pemerintahan reformasi dirumuskan dalam GarisGaris Besar Haluan Negara, namun setelah reformasi dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). GBHN dan RPJPN yang kesemua ini adalah merupakan dokumen politik yang memuat garis atau haluan politik hukum. Sedangkan konsep strategis yang memberikan arahan bagi perumusan garis politik hukum itu sendiri oleh Solly Lubis disebutnya sebagai wawasan politik. Itulah sebabnya Solly Lubis dalam kesimpulannya menyatakan bahwa konsep wawasan politik hukum nasional belum tuntas. Selama konsep wawasan politik hukum nasional belum tuntas, menurut beliau pembangunan hukum akan terus berlarut-larut dengan praktek 462 pembentukan hukum yang tambal sulam yang belum tentu terjamin konsistensinya dengan cita-cita penegakan hukum dan keadilan. 383 Harus ada keberanian untuk melihat kenyataan bahwa hukum bukanlah suatu benda kaku, karena hukum dibuat sengaja oleh manusia (purposefullns) sebagai political will penguasa untuk mengatur kepentingan rakyat dalam negaranya. Karena itu hukum tidak hanya dirumuskan sebagai norma-norma atau doktrin-doktrin akan tetapi juga memuat asas-asas yang secara implisit tersembunyi di belakang atau berada di balik norma hukum itu. Dengan konstruksi yang demikian maka hukum menjadi lebih artifisial daripada natural, seperti pohon yang tumbuh dari biji. Keberanian untuk melihat hukum sebagai konstruksi sosial yang berpangkal pada pilihan politik hukum atau politik kebudayaan dan karenanya hasil konstruksi itu boleh diubah dengan konstruksi baru. Perubahan-perubahan itu telah lazim terjadi di tengah-tengah masyarakat dan itulah sebabnya hukum berubah dari masa ke masa dan dari abad ke abad untuk kepentingan dari generasi ke generasi. Perubahan-perubahan semacam itu dirumuskan dalam dokumen negara yang dicatat sebagai haluan politik hukum negara. Hanya dengan demikian hukum tidak lagi dilihat sebagai benda kaku dan sekumpulan huruf-huruf yang dituangkan di atas kertas. Studi hukum melalui pendekatan sejarah akan dapat membantu untuk sampai pada satu harapan bahwa di depan akan dapat dirumuskan hukum-hukum yang lebih bernuansa humanis dan berkeadila dan menampung berbagai harapan dan cita-cita Negara. Studi sejarah hukum menjadi sangat penting manakala hukum masa lalu dan yang sedang berlaku hari ini belum mampu memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan. Perlunya kajian atau studi sejarah terhadap hukum paling tidak memiliki alasan ilmiah : Pertama : sangat sedikit studi-studi hukum yang dilakukan melalui pendekatan sejarah. Kedua : terjadi keterputusan sejarah yang disebabkan oleh ketiadaan jembatan-jembatan penghubung antara 383 Untuk mewujudkan bangunan hukum nasional yang sesuai dengan dimensi ketatanegaraan Indonesia pembangunan hukum itu harus dilakukan melalui pendekatan sistem. Pembangunan hukum nasional harus diliha sebagai salah satu sub sistem yakni dimensi politik (sub sistem politik) yang secara kontekstual dan konseptual bertalian erat dengan dimensi-dimensi (sub sistem) geopolitik, ekopolitik, demopolitik, sosiopolitik dan kratopolitik. Solly Lubis menegaskan politik hukum tidak berdiri sendiri atau lepas dari dimensi politik lainnya apalagi jika hukum diharapkan mampu berperan sebagai sarana rekayasa sosial. Lebih lanjut lihat M. Solly Lubis, Serba-Serbi Politik & Hukum, PT. Sofmedia, Jakarta, 2011, hal. 54. 463 Ketiga : Keempat : Kelima : generasi sarjana hukum sebelum kemerdekaan, generasi pasca kemerdekaan periode kepemimpinan Bung Karno, generasi pasca kepemimpinan Bung Karno (periode kepemimpinan Soeharto dengan rezim orde barunya), generasi pasca kepemimpinan Soeharto yakni generasi orde reformasi dan generasi orde pasca reformasi sehingga studi-studi hukum yang dilakukan kering dari pembelajaran sejarah dan ini membawa dampak pada terbelenggunya peradaban hukum pada situasi yang pragmatis. Tidak dimasukkannya dalam kurikulum pendidikan hukum pada strata I tentang materi pengajaran sejarah hukum, padahal data sejarah hukum cukup banyak tersebar di berbagai arsip dan perpustakaan. Harus ada yang melanjutkan jembatan yang berisikan narasi sejarah hukum untuk menyambungkan keterputusan sejarah guna dapat memaknai budaya hukum Indonesia yang tepat dalam rangka pilihanpilihan politik hukum guna pembangunan sistem hukum nasional di masa-masa yang akan datang. Tanpa disadari telah terjadi perang kepentingan atau interes antara mereka-mereka yang berfikir pragmatis, praktis, jalan pintas, melawan kepentingan yang memperlihatkan kesadaran hukum yang memberi makna bahwa jatuh bangunnya peradaban mestilah berakhir dengan kemenangan peradaban yang adil dan merujuk pada pilihan ideologi yang telah diletakkan pada saat negara ini didirikan yang mengacu pada the original paradigmatic value of Indonesian culture and society jika kita tidak ingin sejarah hukum kita terputus sebab pembiasan yang dalam tradisi keilmuan dinamai proses internalisasi mengenai yang baik, yang benar, yang indah, yang adil, yang beradab, serta suci bersumber dari kehidupan para tokoh-tokoh yang dapat dijadikan teladan. Beribu-ribu ajaran kognisi pengetahuan dan hafalan tentang teks-teks normatif akan percuma saja apabila sosok yang berjasa dalam meletakkan dasar-dasar pembangunan hukum dalam sejarah kita, yaitu para pendiri bangsa, guru-guru bangsa, mereka-mereka yang secara terus mempertahankan hukum adat dan berbagai 464 pengorbanan demi pengorbanan yang mereka lakukan untuk meletakkan dasar pembangunan hukum bangsa ini. Dan tokoh-tokoh semacam itu saat ini sudah sulit untuk kita temukan. Jika disertasi ini memilih teori yang dikembangkan oleh para akademisi yang dalam karier dan kehidupannya telah menghabiskan masa untuk pembangunan hukum dan pembangunan ilmu hukum seperti, Mahadi dan M. Solly Lubis, serta Hikmahato Juwana ini bukanlah semata-mata untuk memperkenalkan pemikiran-pemikiran mereka - yang satunya hendak membangun hukum Indonesia modern, yang satunya lagi hendak meletakkan dasar pembangunan hukum Indonesia melalui hukum adat sebagai dasar dan terakhir kesemuanya hendaklah diletakkan dalam satu kerangka sistem yang disebut sebagai sistem hukum nasional - akan tetapi lebih jauh menggiring generasi yang akan datang untuk dapat memahami sejarah perjalanan hukum Indonesia, dan di negeri ini ternyata banyak pandangan dan pemikiran yang lahir dari anak bangsa sendiri, yang faham tentang kebutuhan hukum dii negerinya,sebab membangun hukum bukanlah semata-mata melakukan sesuatu akan tetapi mempelajari sesuatu. Dengan lima alasan tersebut di atas, anak bangsa di negeri ini harus punya kemauan dan dengan rendah hati mengakui keterputusan sejarah peradaban hukum - karena kita harus menyadari pula bahwa ingatan kita sangat pendek - dan ketidak pedulian kita sendiri terhadap pilihan-pilihan politik dalam pembangunan hukum nasional. Kini, mari kita rajut kembali benang-benang sejarah yang putus dan mempelajari kembali “situs-situs” yang saat ini memerlukan guru-guru yang dapat memikirkan dan menterjemahkan serta menafsirkan situs-situs itu. Saat ini diperlukan sosok intelektual hukum yang memahami sejarah karena kita tidak ingin terjadi apa yang pernah dikatakan oleh Sartono Kartodirdjo, “jangan menjadi cendekiawan model pohon pisang yang sekali berbuah lalu selesai”.384 Teruslah merajut benang-benang sejarah yang terputus agar untaian-untaian sejarah hukum Indonesia dapat dirajut dalam suatu “kain” yang bermakna lembaran sistem hukum nasional Indonesia. 384 Lebih lanjut lihat Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993. 465 Salah satu kebijakan yang perlu ditempuh dalam pembangunan hukum adalah terciptanya suatu tatanan hukum yang dapat menjembatani kepentingan masyarakat Indonesia yang saling berbenturan sebagai akibat dari tawaran kultur yang plural. Perbedaan pada kultur dan berpengaruh pada budaya hukum ini berawal dari perjalanan sejarah yang cukup panjang yang memperlihatkan adanya pengaruh sistem hukum asing (yang sejak awal juga sudah ada perbedaan yakni antara sistem hukum Eropa Kontinental di satu pihak dan sistem hukum Anglo Saxon di pihak lain) terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (lokal) Indonesia (hukum adat). 385 Paling tidak dengan kebijakan itu perbedaan-perbedaan pada sistem hukum itu dapat sedikit demi sedikit (secara berangsur-angsur) dihapuskan untuk kemudian menuju pada satu tatanan hukum yang dapat berterima dalam kehidupan masyarakat Indonesia namun tetap pula mampu mengantisipasi gelombang globalisasi yang ditawarkan oleh masyarakat internasional. Dengan bahasa yang sederhana harapan dari pilihan terhadap kebijakan yang semacam ini adalah untuk mengukuhkan kembali hukum rakyat sebagai hukum yang hidup agar kepentingan masyarakat tetap terpelihara dengan baik, namun tetap eksis dan mampu menangkap setiap perubahan yang ditawarkan oleh peradaban modern. Apa sebenarnya yang ditawarkan oleh sistem hukum Eropa kontinental yang dalam pilihan terhadap kebijakan pembangunan hukumnya didasarkan pada konsepsi hukum yang terkodifikasi dengan rapi, tidaklah terlalu buruk untuk terus dikembangkan dalam strategi pembangunan hukum di Indonesia, yang dalam banyak hal lebih memberikan kepastian hukum. Namun begitu, apa yang sesungguhnya yang dikembangkan oleh negara-negara penganut sistem hukum Anglo Saxon (Amerika dan Inggris meskipun keduanya ada juga perbedaan), yang menggantungkan pola pilihan dalam penentuan apa yang menjadi hukum melalui putusan hakim, adalah juga sangat sesuai bagi Indonesia. Oleh karena konsepsi hukum Adat Indonesia yang sejak lama didasarkan pada putusan fungsionaris hukum adat (teori Beslissingen Leer yang dikembangkan oleh Ter Haar) 386 adalah sangat 385 Lihat Soetandyo Wignjosoebroto, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Rajawali Press, Jakarta, 1994. 386 Lebih lanjut lihat Ter Haar Bzn, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, (Terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto), Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, dan Jakob Sumarjo, Jakob Sumardjo, Mencari Sukma Indonesia Pendataan Kesadaran Keindonesiaan di Tengah Letupan Disintegrasi Sosial Kebangsaan, AK Group, Yogyakarta, 2003. 466 sejalan dengan konsepsi yang ditawarkan oleh sistem hukum Anglo Saxon. Oleh karena itu pula, memadukan antara kedua kutub yang berbeda itu untuk dipertemukan dalam rangka kebijakan pembangunan hukum Indonesia menurut hemat kami adalah suatu langkah yang arif guna memberi arti bagi hukum rakyat Indonesia sebagai hukum yang hidup. Caranya adalah, mengangkat kembali ”nilai-nilai hukum yang hidup” dalam masyarakat Indonesia, melalui langkah-langkah metodologis yang lazim dikenal dalam ilmu hukum. Wibawa Republik yang sedang dikemudikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono ini hukum dan keadilan, sedang dipertaruhkan, karena itu kembalilah pada komitmen bahwa negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu para legislatif haruslah menjalankan fungsi legislasinya secara benar, punya komitmen kerakyatan, yang berisikan moral dan keadilan dengan mengacu sepenuhnya pada cerminan kultur Indonesia yang berkepribadian bangsa dan para eksekutif haruslah berperan sebagai penerima amanah legislatif, menjalankan amanah yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan, jangan berperan dan mengambil posisi sebagai legislatif (misalnya menerbitkan Keppres, Perda dan lain sebagainya yang bertentangan dengan amanah rakyat) serta para yudikatif hendaklah benar-benar menjalankan fungsi yudisiilnya, tidak justeru berperan sebagai perpanjangan tangan eksekutif. 1. Think Globally Berpikir global (think globally) tidak hanya cukup untuk memusatkan perhatian pada kepentingan bangsa sendiri di tengahtengah bangsa lain yang juga punya keinginan dan hak yang sama. Dunia sudah semestinya tidak lagi dihiasi dengan peperangan. Politik ekonomipun sudah semestinya tidak lagi mengarah pada kepentingan dan keinginan negara-negara maju saja tanpa memperhatikan kepentingan negara berkembang. Peperangan selama ini berlangsung di berbagai belahan dunia, tidak lebih dari sebuah kerakusan kekuasaan yang hendak mengeksoploitasi kekayaan alam dan berbagai potensi strategis guna mengamankan kepentingan negara maju. Negara industeri maju, sesungguhnya tidak dapat bertahan tanpa negara negara dunia ketiga yang mengkonsumsi produk industeri mereka. Jika negara dunia ketiga dibiarkan miskin, siapa yang harus berbelanja untuk membeli produk industeri mereka. Ketika industri perfilman Amerika maju pesat, karya sinematografi yang dilindungi hak ciptanya itu harus menembus pasar di negara-negara berkembang. Demikian pula produk industri otomotif, 467 elektronik dan industri kimia serta kedirgantaraan harus dilempar ke pasar-pasar negara-negara di dunia ketiga. Adalah tidak pada tempatnya jika kemudian negara-negara konsumen itu diperlakukan tidak adil. Peperangan yang bergolak sepanjang sejarah dunia di kawasan Timur Tengah, tidak lebih dari sebuah “permainan” politik Amerika yang secara terus mnenerus memasok persenjataan, hingga Amerika kemudian menempati peringkat atas sebagai negara produsen senjata dan di dalam negerinya industri senjata menempati peringkat pertama sebagai industri strategis. Di luar dugaan kemudian Amerika harus menjadi motor dalam kampanye perlindungan Hak azasi Manusia dan issu lingkungan. Adalah Indonesia sebagai negara pemilik hutan tropis terbesar setelah Brazil yang dalam konvensi Rio de Janeiro dan dikukuhkan dalam Protokol Kyoto, untuk terus mempertahankan hutan tropis sebagai paru-paru dunia. 387 Sementara negara-negara Industeri terus menerus menyumbangkan CO2 (karbondioksida) ke udara dan negara pemilik hutan tropis terus menerus diminta untuk menyumbangkan O2 (oksigen) ke udara. Banyak kritik pedas yang diarahkan pada negaranegara Industeri maju, tapi mereka tidak bergeming karena dunia telah didominasi oleh kekuatan politik liberal dan kekuatan ekonomi kapitalis. Suara-suara dari kelompok dunia ketiga, akhirnya tenggelam dan sirna dalam berbagai konvensi dan pertemuan Internasional. Pemenangnya tetap negara Industri maju dan negara miskin cukup berpuas hati sebagai negara yang diundang dalam pertemuan sebagai pendengar yang budiman. Banyak kasus yang menunjukkan loby-loby Internasional yang dilakukan oleh negara negara dunia ketiga kandas karena keputusan selalu didominasi oleh negara-negara maju yang cenderung kapitalis sebagaimana diungkapkan oleh Robert Gilpin388 yang menyatakan : The World Trade Organization (WTO) is, in essence, an American creation. The WTO’s predecessor, the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) had served well America’s fading mass-production economy, but it did not serve the emerging economy equally well. As a consequence of economic and technological developments prior to the Reagan Administration, the United States had become an increasingly serviceoriented and high-tech economy. Therefore, in a major effort to reduce trade barriers, the Uruguay Round was initiated by the Reagan Administration and 387 Lebih lanjut lihat Michael B. Gerrard, (ed), Global Climate Change and U.S.Law, American Bar Association Section of Environment, Energy and Resources, Chicago, 2007. 388 Robert Gilpin, Global Political Economy Understanding The International Economic Order, Princeton University Press, New Jersey, 2001, hal. 222-223. 468 later was supported by the Bush Administration and, after much vacillation, by the Clinton Administration as well. Semakin pasti bahwa organisasi perdagangan dunia adalah merupakan gagasan Amerika, untuk mengantisipasi perekonomian Amerika yang berbasis pada jasa dan produk-produk industri yang berteknologi tinggi. Antisipasi itu lebih dimaksudkan untuk mengurangi hambatan perdagangan yang diprakarsai oleh Reagen dan kemudian didukung oleh Pemerintahan Bush karena kondisi sebelumnya hal itu tidak dimungkinkan sebab pemerintahan Clinton selalu ragu dalam mengambil keputusan. Langkah yang diambil oleh Amerika ini pada akhirnya telah menciptakan kapitalisme global seperti yang diungkapkan oleh Frieden. 389 Meskipun kemudian dalam hal perdagangan bebas di era Global Paul 390 berpendapat lain ; A political argument for free trade reflects the fact that a political commitment to free trade may be a good idea in practice even though there may be better policies in principle. Economists often argue that trade policies in practice are dominated by special-interest politics rather than consideration of national costs and benefits. Economists can sometimes show that in theory a selective set of tariffs and export subsidies could increase national welfare, but in reality any government agency attempting to pursue a sophisticated program of intervention in trade would probably be captured by interest groups and converted into a device for redistributing income to politically influential sectors. If this argument is correct, it may be better to advocate free trade without exceptions, even though on purely economic grounds free trade may not always be the best conceivable policy. The theree arguments outlined in the previous section probably represent the standard view of most international economists, at least in the United States ; 1. The conventionally measured costs of deviating from free trade are large. 2. There are other benefits from free trade that add to the costs of protectionist policies. 3. Any attempt to pursue sophisticated deviations from free trade will be subverted by the political process. Nonetheless, there are intellectually respectable arguments for deviating from free trade, and these arguments deserve a fair hearing. Krugman dan Obstfeld dengan tegas mengatakan, bahwa kebijakan ekonomi Internasional yang dilancarkan, tidak lebih dari sebuah dominasi politik kepentingan, akan tetapi dicari alasan-alasan 389 Lebih lanjut lihat Jeffry A. Frieden, Global Capitalism Its Fall and Rise in The Twentieth Century, W.W. Norton & Company Inc, New York, 2007. 390 Paul R. Krugman and Maurice Obstfeld, International Economics Theory and Policy, Pearson Education Inc, Boston, 2003, hal. 221. 469 yang masuk akal. Politik ekonomi Internasional yang dituangkan dalam berbagai kesepakatan Internasional seperti GATT/WTO adalah sebuah perebutan hegemoni kekuasaan yang berujung pada imperialisme. Banyak teori yang berkisah tentang itu seperti teori liberal dan teori “iblis” tentang imperialisme. 391 Teori-teori sosial tampaknya telah gagal memahami jalan pikiran keuasaan negara-negara ekonomi maju. Ibarat sebuah pengusaha industry manufactur menguasai hulu sampai hilir mata rantai industrinya, mulai penyediaan bahan baku sampai pada pemasaran, sehingga tidak memberi celah bagi orang lain untuk dapat hidup, kecuali menjadi konsumen sejati. Jika ada pihak yang ingin memutus mata rantai itu, negara-negara itupun sudah siap untuk berperang. Akhirnya bumi semakin hari semakin jauh dari rasa nyaman untuk ditinggali. Padahal yang dikehendaki oleh umat manusia dalam perspektif hukum adalah rasa nyaman, rasa aman, dunia dapat lebih sejahtera dengan rasa keadilan serta jauh dari rasa ketidak pastian. Perbedaan dalam kehidupan di dunia di alam global sebenarnya adalah suatu rahmat. Menyimpang dari teori ilmu sosial, tanpa keraguan premis Al Qur’an dapat dijadikan rujukan : Al Hud 118, Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Al Maidah 48 Sekiranya Allah menghendaki niscaya kamu dijadikanNya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberinya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Al Hujarat 13, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsabangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal 391 Uraian lebih lanjut mengenai hal ini lihat Hans J. Morgenthau, Politik Antarbangsa, (Terjemahan S. Maimoen dkk), Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 66. 470 mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Ketiga ayat Alqur’an di atas telah menyentakkan kesadaran manusia, bahwa jika sesungguhnya Tuhan menghendaki, ia dapat menjadikan ummat di muka bumi ini menjadi ummat yang satu. Kemahakuasaannya tidaklah mungkin Tuhan tidak dapat menciptakan umat manusia menjadi satu entity, akan tetapi sekali lagi perbedaan itu rahmat, agar manusia dapat berinteraksi dengan adanya perbedaan itu. Dalam ketiga ayat itu tersembunyi azas yang disebut sebagai “spirit of pluralism”. Perbedaan itu fitrah hasil ciptaan Allah. Indonesia telah lama menerima perbedaan itu yang dituangkan dalam adagium Bhinneka Tunggak Ika dan disahuti dengan baik oleh Pancasila sebagai “mietsaqon khalidza” atau modus vivendi atau kesepakatan luhur nasionalisme. Hal semacam itu telah dipraktekkan oleh Rasullallah Muhammad SAW ketika memimpin negara di Madinah yang dituangkan dalam konstitusi yang disebut dengan Konstitusi Madinah. 392 Manusia telah ditetapkan oleh Allah menjadi khalifah di muka bumi yang diberi tugas untuk memakmurkan bumi, karena itu pilihlah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil dan amanah adalah syarat untuk dapat memakmurkan bumi. Bahkan Imam Ghazali pernah berkata, pemimpin yang tidak muslim tapi ia berlaku adil dan mengemban amanah jauh lebih baik dari pemimpin muslim tapi zalim. 393 Yang terasa hari ini adalah munculnya pemimpin yang zalim di sekala lokal dan skala Internasional. Akibatnya bumi masih menunggu lagi, apakah ia musnah lebih awal atau masih ada manusia yang mau dan berkeinginan untuk mempertahankannya, karena Allah menyatakan, kerusakan di bumi dan di langit adalah karena ulah perbuatan manusia sendiri (QS : Ar-Rum 41). Karena itu manusia yang hidup di muka bumi harus berkompromi untuk menyelamatkannya. Tidak justeru saling mengeksploitasi dan mengeksplorasi. Dalam tatanan kehidupan global, harus ada ilmuwan sosial yang duduk berbagi pengalaman untuk menciptakan tatanan kehidupan dunia yang lebih berkeadilan. Sebuah tatanan yang dituangkan dalam kesepakatan dunia yang think globally. 392 Lebih lanjut lihat Muhammad Hussein Haekal, Sejarah Hidup Muhammad, (Penerjemah : Ali Audah), Litera Antar Nusa, Jakarta, 2008, hal. 202-205. 393 Pernyataan ini tidak bermaksud melahirkan perdebatan, sekali lagi hal ini diluar otoritas keilmuan penulis, akan tetapi yang hendak ditekankan di sini adalah betapa dunia di era globalisasi ini menghendaki pemimpin yang adil. 471 Persoalan yang paling pelik dalam analisis ilmu-ilmu sosial adalah ketika menghubungkan fenomena global dengan ancaman ideologi.394 Ancaman-ancaman ideologi tidak terlepas dari sejarah pencerahan yang dikenal dengan revolusi ilmu pengetahuan. Revolusi ilmu pengetahuan berawal di Perancis, yang dikenal dengan abad pencerahan (elightenment). Revolusi industeri-pun berpangkal di Perancis395 Eropa di bawah penaklukan Napoleon Bonaparte sekalipun kekuasannya tealh berakhir, tetapi telah berhasil menanamkan benihbenih ilmu pengetahuan dengan metodologinya yang khas yakni, lepas dari pengaruh agama, mistik dan metafisik. Ilmu pengetahuan harus bersih dari prasangka non-ilmiah, ilmu pengetahuan harus bebas nilai. Akan tetapi secara mengejutkan, hukum-hukum yang diteruskan pasca Revolusi Perancis, justeru bukan hukum yang bersumber dari ilmu pengetahuan itu, tapi justeru hukum yang syarat dengan nilai. Nilainilai kristiani masih mewarnai sebahagian besar hukum Eropa yang bersumber dari Code Civil Prancis.396 Globalisasi seharusnya tidak menggusur negara-negara miskin atau negara-negara dunia ketiga, oleh negara maju. Pernyataan ini diawali dari banyaknya kecurigaan yang datang dari negara dunia ketiga atas gagasan negara-negara maju untuk menerapkan intrumen hukum internal dalam kebijakan perdagangan dunia. Pertanyaan bagi Indonesia adalah apakah kita hidup dalam pergaulan Internasional di bawah bayang-bayang kecurigaan itu ? Jika 394 Pada awal abad ke-18 untuk pertama kalinya istilah ideologi dikenal dalam dunia akademis. Istilah ini dipergunakan oleh Anthonie Destutt de Tracy (1754-1836) dalam karya-karyanya meskipun jika dirunut ke belakang pemaknaannya dapat juga ditemukan dalam tulisan Francis Bacon (1561-1626), Niccolo Machiavelli (1469-1520) dan Plato (429-347 SM). De Tracy memaknai istilah ideologi sebagai ilmu pengetahuan tentang ide-ide. Ideologi menurutnya adalah dasar bagi pendidikan dan ketertiban moral (moral order). Dalam perspektif positif, ideologi dilihat sebagai suatu ilmu yang melampaui prasangka-prasangka agama dan metafisika serta menjadi landasan bagi penentuan aturan moral. Kosa kata ideologi yang dipergunakan oleh De Tracy memiliki akar historis dan tradisi pencerahan Prancis yang menganut pandangan bahwa akal adalah alat untuk mewujudkan kebahagiaan yang utama. Lebih lanjut lihat Ian Adam, Ideologi Politik Mutakhir Konsep, Ragam, Kritik dan Masa Depannya, Qalam, Yogyakarta, 2004, hal. vii. 395 Lebih lanjut lihat Thomas Carlyle, The French Revolution a History, The Modern Library, New York, 2002. 396 Lihatlah di lapangan hukum perkawinan, penerapan azas monogami, ikatan dalam perkawinan, demikian juga dalam lapangan hukum perikatan mengenai saksi yang harus dihadiri dua orang, azas iktikat baik, asas partij otonomi, dan lain-lain sebagainya. Demikian juga etik Protestan sebagaimana ditulis Weber, juga menjadi dasar dalam berbagai kontrak dan perjanjian perburuhan. Lebih lanjut lihat Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism with other Writings on the Rise o the West, Oxford University Press, New York, 2009. 472 tidak, masih mungkinkah Indonesia dapat mewujudkan cita-cita kemerdekaannya di tengah arus globalisai tersebut ? Apakah negara ini perlu berpikir untuk kepentingan globalisasi tersebut (think globally) ? Siapa Amerika, siapa Jepang, Kanada, Inggeris, Prancis dan siapa negara-negara G-8, dan apa kontribusinya bagi Indonesia sehingga negeri ini perlu memikirkannya? Sekalipun banyak tulisan yang mengungkapkan, bahwa globalisai itu hanyalah mitos, globalisasi adalah sebuah kehampaan, globalization is nothing, globalization its discontents, akan tetapi globalisasi telah banyak merubah pandangan dan peradaban dunia. Jika globalisasi dimaknai sebagai sebuah gejala atau fenomena peradaban yang menyebabkan dunia terasa semakin menyempit, bebas dari sekatan dinding-dinding nasional, maka tidak dapat dipungkiri globalisasi akan menjadi topik diskusi menarik dalam ilmu-ilmu sosial. Akan banyak kebijakan politik, ekonomi dan kebudayaan yang akan bertolak dari rumusan globalisasi itu. Jika tidak ada lagi sekatan perdagangan antar negara, maka kaedah hukum seperti apa yang harus dipersiapkan untuk mengatur hubungan hukum semacam itu. Tentu tak perlu lagi ada pembatasan hukum apabila nelayan Indonesia menjual hasil tangkapannya di tengah laut dengan nelayan Thailand atau nelayan Malaysia. Suatu hari persoalan nilai tukar mata uangpun tidak menjadi persoalan, jika di kemudian hari kelak (sebagai dampak dari globalisasi) di negara-negara Asean terwujud satu mata uang seperti di Masyarakat Ekonomi Eropa. 2. Commit Nationaly Gagasan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan adalah sebuah gagasan yang hanya dapat diwujudkan apabila didukung oleh iklim politik ekonomi dan sosial budaya yang kesemuanya memberikan sumbangan positif dan secara simultan bekerjasama untuk mencapai tujuan dimaksud. Iklim politik yang tidak mendukung yang selama kurun waktu bertahun-tahun penuh dengan carut marut telah membawa bangsa ini jauh kedalam keterpurukan. Demikian juga pilihan politik atau kebijakan ekonomi yang bersumber dari faham kapitalis-liberal telah menciptakan jurang yang dalam antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin. Kondisi ini sebenarnya adalah berpangkal pada perjalanan sejarah masa lalu bangsa ini dan itu tidak terlepas dari perjalanan sejarah tata hukum nasional. 397 Perkembangan tata hukum 397 Pemaknaan tata hukum lebih luas dari sekedar arti atau makna yang dikandung dalam istilah sistem hukum. Tata hukum yang dimaksud disini adalah 473 nasional demikian tulis Soetandyo398 adalah perkembangan yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan kapitalis-liberal yang mencoba untuk membuka peluang-peluang lebar pada dan untuk modal-modal swasta dari Eropa guna ditanamkan kedalam usaha-usaha perkebunan besar di daerah jajahan, namun juga dengan maksud di lain pihak untuk tetap melindungi kepentingan desa-desa dan pertanian tradisional yang menjadi sumber kehidupan penduduk pribumi. Sebuah langkah politik yang sangat kontradiktif. Di satu pihak, perkebunan besar yang luas dibuka, namun di pihak lain masyarakat diberikan hak-hak yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk kasus Sumatera Timur misalnya areal perkebunan tembakau dibuka lebar dengan menggusur hak-hak masyarakat adat yang kala itu hanya diberikan hak untuk bercocok tanam pada satu tahun musim tanam pada saat tanah tidak ditanami tembakau (masa bera) untuk bercocok tanam padi atau jagung. Tanah tempat bercocok tanam itu dikemudian hari dikenal sebagai tanah jaluran dan rakyatnya dikenal dengan sebutan rakyat penunggu. 399 Yang hendak dijelaskan dari kasus rakyat penunggu ini adalah kebijakan kapitalis – liberal yang dilancarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dikemudian hari telah menjadi sumber kemiskinan yang pada putaran sejarah berikutnya menyumbangkan kemiskinan struktural. Eksploitasi terhadap buruh perkebunan yang sesungguhnya belum berakhir sampai hari ini pasca perkebunan itu dinasionalisasi adalah satu contoh konkrit warisan dari kebijakan kapitalis-liberal yang didalamnya juga tersembunyi feodalism dan imperalism. Masyarakat tradisional yang notabene adalah puak Melayu telah kehilangan hakhaknya untuk menjadi petani di atas lahannya sendiri, karena lahanlahan itu kemudian meminjam istilah Edy Ikhsan “dirampok” oleh negara untuk dan atas nama nasionalisasi pada tahun 1958, untuk dan atas nama pembangunan pada era Soeharto, untuk dan atas nama keseluruhan norma-norma yang diakui masyarakat sebagai kaedah yang mengikat demi tercapainya ketertiban kehidupan dalam masyarakat dan karena itu dipertahankan berlakunya oleh suatu otoritas – untuk fungsi itu – yang juga diakui oleh masyarakat. Karena itu tata hukum tidak hanya menyangkut kaedah hukum normatif dengan prosedur yang spesifik yang dikenal dalam sistem hukum akan tetapi juga keseluruhan aturan yang bersumber dari kaedah-kaedah sosial seperti adat istiadat, kebiasaan, agama dan lain-lain yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Model penegakannyapun tidak hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum formal, tetapi boleh jadi dilakukan oleh tokoh-tokoh informal dalam masyarakat itu. 398 Soetandyo Wignjosoebroto, Op.Cit, hal. 3. 399 Lebih lanjut lihat Edy Ikhsan, Antan Patah Lesungpun Hilang : Pergeseran Hak Tanah Komunal dan Pluralisme Hukum Dalam Perspektif Sosio-Legal (Studi Pada Etnis Melayu Deli di Sumatera Utara), Disertasi, Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum – Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013. 474 negara pada era-era pemerintahan berikutnya. Banyak nilai-nilai hukum adat dan nilai-nilai moral yang hilang ketika perampokan tanah ulayat masyarakat adat itu dilakukan oleh pemerintah. Kehilangan nilai-nilai itu dikemudian hari menyeruak kembali dan terjadi penggarapan tanah secara liar di atas lahan-lahan perkebunan itu dengan menggunakan jargon untuk dan atas nama hak ulayat akan tetapi di belakangnya berdiri tegak “cukong-cukong” dan “mavia tanah”. Terdapat ketidak jelasan pilihan politik hukum nasional untuk melindungi hak-hak warga negara yang didistribusikan secara adil. Bahwa perlindungan terhadap hak-hak warga negara itu secara kasat mata memang tampaklah telah dilakukan, misalnya saja prinsip nasionalitas yang dianut oleh Undang-undang Pokok Agraria. Tidaklah mudah untuk melepaskan hak-hak atas tanah kepada orang asing akan tetapi dalam praktek yang sesungguhnya perlindungan hukum yang diberikan kepada kelompok Bumi Putera tidak diberikan secara adil kepada petani atau masyarakat tradisional yang sesungguhnya berhak atas kekayaan alam itu. Perkebunan-perkebunan besar saat ini telah terbentang luas, dimana kepemilikan sahamnya dimiliki oleh warga negara asing. Demikian juga sebahagian dari kondominium dan rumahrumah mewah serta plaza-plaza yang berdiri di perkotaan sesungguhnya dimiliki oleh warga negara asing. Asas nasionalitas tidak terang betul melekat dalam praktek kepemilikan sumber kekayaan alam bangsa ini. Belajar dari kasus tersebut adalah sebuah kearifan jika hukum Indonesia masa depan memiliki kemampuan untuk memberikan proteksi terhadap warga negara terutama masyarakat asli atau dengan menggunakan terminologi dari Mahathir Muhammad, Perdana Menteri Malaysia yang dalam berbagai kebijakannya telah memberikan perioritas kepada penduduk bumi putera. Fasilitas itu tidak hanya dalam bentuk penyediaan lahan-lahan pertanian dengan memberikan bibit, pupuk, akan tetapi juga meliputi seluruh fasilitas seperti pendidikan, kesehatan dan akses ke dunia perbankan. Mahathir Muhammad dengan konsep pembangunannya “berpaling ke Asia” telah berhasil mengangkat tingkat kehidupan masyarakat Malaysia di atas rata-rata kesejahteraan masyarakat ASEAN setelah Singapura. Mahathir Muhammad berhasil mengukuhkan jati diri bangsanya dan dengan terang-terangan berhadapan dengan Amerika yang selalu disebutnya sebagai “pengacau”. Dalam lapangan hak kekayaan intelektual, Malaysia telah memilih politik hukum yang berbeda dengan Indonesia, namun sama pilihannya dengan Cina dan India. Jadi tidak serta merta dan terburu- 475 buru menyetujui dan melaksanakan tuntutan negara-negara maju yang merupakan hasil capaian putaran Uruguay Round yang tertuang dalam TRIPs Agreement. Sikap berbeda yang diambil oleh Malaysia dan beberapa negara tadi adalah karena pertimbangan-pertimbangan kepentingan nasional. Tahun-tahun yang dilalui oleh Indonesia pasca ratifikasi GATT 1994/WTO yang menghasilkan salah satu instrumen hukum HKI yakni TRIPs Agreement, adalah tahun-tahun dimana Indonesia disibukkan dengan penyempurnaan undang-undang nasionalnya dengan tuntutan konvensi tersebut. Tidak sedikit juga waktu yang terbuang diikuti dengan biaya dalam penyempurnaan undang-undang itu yang diikuti dengan membuat persetujuan-persetujuan bilateral dengan berbagai negara, khususnya negara Eropa yang beberapa tahun belakangan ini merasa dirugikan dengan perilaku pembajakan karya sinematografi. Hasil-hasil konfrensi diplomatik misalnya dijadikan dasar untuk membuat kesepakatan atau traktat bilateral. Kadangkadang rumusan yang dibuat dalam kesepakatan itu sangat sederhana yang intinya pada tataran basic policy menyetujui saja konvensi internasional yang bersumber dari hukum kapitalis-liberal.400 Tapi langkah ini bukan tidak membawa konsekuensi, sebab pada saat kesepakatan bilateral itu diterapkan, kemandirian negara boleh jadi menjadi hilang. Hilang karena ada bahagian yang paling asasi dalam kesepakatan itu yang tidak dapat dimaknai karena roh atau jiwanya berbeda. Seorang yang ingin mandiri, dia hanya dapat hidup dengan jiwanya sendiri, dengan keiunginannya sendiri, dengan pertimbangan dan keputusannya sendiri tanpa diintervensi pihak lain. Akan tetapi mandiri yang berarti melepaskan ketergantungan dengan pihak lain harus memiliki beberapa syarat. Paling tidak, ketergantungan secara politik, ekonomi dan keamanan telah dapat dilepaskan dari bangsa lain seperti yang digagas oleh pendiri bangsa ini. Berdikari, itu adalah ungkapan Bung Karno pada masa-masa awal pemerintahannya untuk menguatkan gagasannya tentang melepaskan ketergantungan Indonesia secara ekonomis dan politis terhadap dua kekuatan raksasa dunia ketika itu. Kekuatan raksasa Amerika (Blok Barat) dan kekuatan raksasa Uni Soviet (Blok Timur). 400 Lihatlah dua buah Keputusan Presiden : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works tanggal 7 Mei 1997 dan : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2004 tentang Pengesahan WIPO Performances and Phonograms Treaty, 1996 (Traktat WIPO Mengenai Pertunjukan dan Rekaman Suara, 1996), tanggal 10 September 2004. 476 Sebagai sebuah negara bangsa, Indonesia harus melepaskan ketergantungannya dari tarikan-tarikan politis dan janji-janji pembangunan mulai dari pinjaman dan bantuan keuangan, tenaga ahli sampai pada bantuan militer. Berdiri di atas kaki sendiri, membangun negara di atas kekuatan dan potensi sumber ekonomi negara yang ada. Kemandirian adalah jargon politik yang dikumandangkan Bung Karno dalam tiap-tiap kesempatan pidatonya di berbagai tempat. Kenyataannya Bung Karno gagal dalam pelaksanaannya. Pembangunan bidang hukum oleh Bung Karno tidak diletakkan sebagai sesuatu yang fundamental sekalipun dia mengatakan bahwa hukum yang dibangun itu harus bersandar pada hukum rakyat seperti ungkapannya berikut ini dalam sambutannya pada Seminar Hukum Nasional Ke-1 di Jakarta tahun 1963 : Saudara-saudara sebagai sarjana hukum harus memupuk hukum according to the feelings wishes of the people, ya, buat apa kita bikin hukum lain, tetapi saudara-saudara dalam hal mengikuti rakyat ini, yaitu tutwurinya tut itu, tutwuri artinya ikut dari belakang, tut, membuntut, wuri dari buri, dari belakang. Saudara-saudara mengikuti rakyat dari belakang sambil melihat apa kehendak rakyat, apa yang jadi perasaan rakyat, apa yang menjadi respect dari rakyat, apa yang menjadi aktivitas rakyat dan segala-gala hal, segala-gala sesuatunya. 401 Bung Karno sekalipun mengatakan hukum itu perlu, tapi pada bahagian pidatonya yang lain beliau lebih menekankan aspek politik. Lebih banyak berbicara tentang revolusi dengan mengambil contoh pada revolusi Kuba. Beliau mengatakan : Revolusi Nasional. The Indonesian revolution is an Indonesian revolution, sebagaimana dikatakan oleh Fidel Castro : The Cuban revolution is an Cuban revolution. Kalau saudara-saudara mau menilai revolusi Cuba dengan …. Begitu banyak di situ orang Sovyetnya gagal, meleset saudara-saudara. Kalau saudara-saudara hendak menilai revolusi Cuba dengan membandingbandingkan idealnya mengenai kultur dengan kultur yang berada di negeri Spanyol meleset saudara-saudara. Revolusi Kuba adalah satu revolusi Kuba. Revolusi Kuba dalam segala facetnya dapat diperas menjadi satu perkataan : Revolusi nasional Kuba. Maka revolusi kitapun demikian. Revolusi adalah revolusi nasional Indonesia. 402 Sekalipun Indonesia berhasil mencetuskan gagasan Non-Blok, akan tetapi Indonesia terseret ke dalam Blok Cina, dan Blok Soviet (Blok komunis) yang tumbuh sebagai kekuatan dunia baru ketika itu. Sampai akhirnya runtuh kekuasaan Bung Karno, Indonesia tak pernah 401 402 Simorangkir, Serba-Serbi LPHN/BPHN, Binacipta, Jakarta, 1980, hal. 164 Ibid, hal. 161. 477 memperlihatkan kemandiriannya. Soeharto sebagai pengganti Bung Karno, karena sejak awal Bung Karno telah mengukuhkan “permusuhannya” dengan Amerika meluncur naik ke tahta pemerintahan.Adalah Amerika yang dengan setia menjadi “pengawal” politik Soeharto yang dikenal dengan pemerintahan Orde Baru. Sedikit demi sedikit Soeharto mulai mencurahkan perhatiannya pada pembangunan ekonomi, tapi minim perhatian dalam bidang pembangunan hukum. Politik menjadi “panglima” pada masa Bung Karno diteruskan oleh Soeharto dengan menambah porsi pada pembangunan bidang sosial dan ekonomi, tapi tetap saja menganggap ringan terhadap porsi pembangunan hukum. Untuk alasan pertumbuhan dan stabilitas dan yang kemudian dikenal sebagai trilogi pembangunan. Pembangunan bidang hukum kemudian menjadi terabaikan ditumpangkan pada sub bidang pembangunan sosial budaya. Hukum hanya menjadi alat untuk menjastifikasi tindakan penguasa. Ketika kekuasaan dibayang-bayangi oleh kekuatan Asing (mungkin karena ketergatungan pinjaman luar negeri atau ketergantungan dalam kebijakan pertahanan dan keamanan atauketergantungan dalam menjalankan politik luar negeri) kemandirian menjadi hilang. 403 Setelah begitu banyak dana,waktu dan sejumlah personil militer yang jatuh korban, akhirnya wilayah itupun harus dilepaskan pada masa-masa awal pemerintahan Habibie dengan sebuah referendum. Ucapan “thank you” dari pihak Amerika tak cukup mampu mengobati berbagai kerusakan mental anak bangsa yang pada masa awal kemerdekaannya mencantumkan kalimat “penjajahan di muka bumi harus dihapuskan” dalam pembukaan UUD nya. Itulah resiko sebua