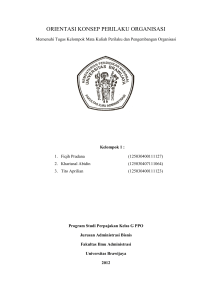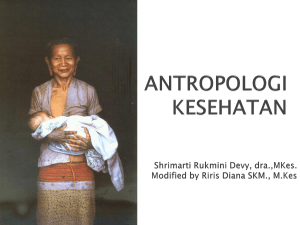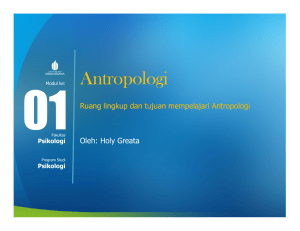Ahimsa, dalam teropong Filsafat Antropologi
advertisement

i/ Ahimsa, dalam teropong Filsafat Antropologi AHIMSA dalam teropong Filsafat Antropologi I Nyoman Yoga Segara Cover Design : M. Setia Lay Out : N. Bakti Cetakan: I /Mei 2017 ISBN : 978-602-9138-90-0 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang Penerbit : CV. Setia Bakti Jl. Padma 30 Penatih Denpasar Timur [email protected] Isi di luar tanggung jawab percetakan PT. Mabhakti v/ Ahimsa, dalam teropong Filsafat Antropologi SENARAI ISI Kata Pengantar Prof. Dr. Ida Bagus Gede Yudha Triguna, MS. (Guru Besar Sosiologi Universitas Hindu Indonesia) ..................... xi UCAPAN TERIMA KASIH .............................................................xvii Senarai Isi................................................................................................ xxiii PROLOG: Filsafat Antropologi dalam Gerakan Moral Ahimsa 1 BAGIAN SATU: Mengapa Ahimsa? ................................................................................. 9 BAGIAN DUA: Mahatma Gandhi dan Pengaruh Sosial-Politik ................ 23 A. Situasi Sosial-Politik di Afrika Selatan, Sebuah Titik Balik ...............................................................................................24 B. Diskriminasi terhadap Warga Negara Kulit Hitam Asia (India) .................................................................... 25 C. Penjajahan Inggris dan Perang Boer .............................................. 28 D. Situasi Sosial-Politik di India........................................................... 31 1. Penjajahan Inggris ........................................................................... 32 2. Konflik Agama (Hindu dan Islam) ............................................. 38 E. Dampak Perang Dunia I dan II ....................................................... 40 BAGIAN TIGA: Dasar Pemikiran Ahimsa dan Tinjauan Filosofis Terhadapnya ..................................................................... 45 xxiv/ Ahimsa, dalam teropong Filsafat Antropologi A. Mahatma Gandhi: Sejarah Hidup, Tradisi, dan Agamanya ............................................................................................46 1. Jaina dan Keteguhan Tradisi .....................................................49 2. Menjadi Manusia-Kosmis dan Penghambaan Total 51 3. Tentang Pelepasan Diri ..............................................................54 4. Pengaruh Samkhya tentang Dualisme ................................... 55 5. Dua Kitab Favorit: Bhagavad-Gita dan Upanisad .............. 56 6. Belajar Selaras dari Buddhisme ............................................... 61 B.Mahakarya Mahatma Gandhi: Dari Satyagraha Menjadi Ahimsa.................................................................................... 62 C. Visi Agung Gandhi tentang Gerakan Non-Kekerasan............... 66 D. Tinjauan Filosofis terhadap Gerakan Ahimsa ............................ 69 1. Tinjauan Metafisika....................................................................... 69 2. Tinjauan Filsafat Antropologi .................................................... 75 BAGIAN EMPAT: Ahimsa sebagai Gerakan Moral dan Resolusi Konflik ....................................................................................................... 83 A. Ahimsa sebagai Bentuk Kesadaran Etis ......................................... 83 B. Ahimsa untuk Emansipatori.............................................................. 87 1. Penghargaan terhadap Martabat Manusia ............................. 88 2. Nilai Fundamental Cinta Kasih ................................................. 91 C. Ahimsa sebagai Resolusi Konflik Sosial-Politik.......................... 93 D. Ahimsa sebagai Anti-Tesa Kekerasan ......................................... 101 1. Kekerasan Struktur dan Kekerasan Langsung ....................103 2. Tiga Pola Menghadapi Kekerasan ..........................................106 3. Bagaimana Pola Gandhi menghadapi Kekerasan? ... 109 xxv/ Ahimsa, dalam teropong Filsafat Antropologi BAGIAN LIMA: Pengakuan Dunia atas Keagungan Nilai Ahimsa .......... 117 A. Buku Manual Ahimsa Bagi Pejuang Hak-Hak Kemanusiaan ...................................................................................... 118 1. Martin Luther King Jr ................................................................120 2. Dalai Lama..................................................................................... 123 3. Laureate Nelson Mandela .........................................................124 4. Aung San Suu Kyi ........................................................................ 125 5. Cesar Chavez ................................................................................. 127 B. Ahimsa dalam Bidang Pemerintahan, Politik dan Kemasyarakatan .......................................................... 129 C. Relevansi Gerakan Moral Ahimsa dalam Kehidupan Sekarang ........................................................................ 133 BAGIAN ENAM: Diskusi Kritis dalam Pemikiran Gandhi............................. 143 A. Kritik Filsafat Manusia atas Jiwa-Badan ............................ 144 B. Kritik Eksistensialisme atas Kesalingterjalinan.................148 C. Kritik Para Penentang dan Lawan-Lawan Politik Gandhi .............................................................................150 BAGIAN TUJUH: Simpulan ............................................................................................... 155 EPILOG: Ahimsa, dari Gerakan Massa ke Individual ...................... 161 Indeks ......................................................................................................... 165 Daftar Pustaka ......................................................................................... 167 Tentang Penulis ....................................................................................... 173 xxvi/ Ahimsa, dalam teropong Filsafat Antropologi PROLOG: Filsafat Antropologi dalam Gerakan Moral Ahimsa ...................................................................................................................................................................... Dalam banyak rujukan, tidak kokoh benar penggunaan istilah antropologi dalam filsafat, meskipun dalam kefilsafatan, antropologi mendapat tempat khusus saat dikaitkan dengan masalah-masalah kemanusiaan. Dari sini muncul istilah Filsafat Antropologi dan Antropologi Filsafat. Keduanya bahkan digunakan secara bolak balik, tergantung titik awal melangkah, apakah dari antropologi atau filsafat. Namun yang sedikit jelas, kedua istilah ini mengandung pesan bahwa masalah manusia dan kemanusiaan menjadi lapangan analisisnya. Dalam buku ini, secara konsisten akan digunakan Filsafat Antropologi, oleh dua sebab. Pertama, ada hubungan yang sangat erat antara filsafat dan antropologi. Ontologi sebagai salah satu cabang utama filsafat–selain epistemologi dan aksiologi–adalah antropologi yang secara khusus membahas manusia dengan segala seluk beluknya, termasuk pertanyaan kritis tentang siapakah manusia itu, apa hakikat manusia, atau bagaimanakah hubungan manusia dengan sesama dan alam. Bahkan antropologi menjadikan manusia sebagai lapangan studinya yang paling utama, terutama tentang asal-usulnya dan bagaimana cara manusia itu hidup. Kedua, filsafat manusia sebagai bagian dari struktur filsafat yang sangat penting, adalah filsafat yang secara luas membahas esensi manusia sebagai kesatuan integral dari seluruh potensi yang ada dalam diri manusia, entah manusia sebagai makhluk pribadi, sosial, hingga makhluk religius. Melalui dua alasan itu, penulis ingin memastikan bahwa antara filsafat manusia dengan antropologi adalah hubungan integral, kalau tidak bsia disebut satu kesatuan, yang mengacu pada keanekaragaman khas fisik manusia dan perkembangannya yang dipusatkan pada struktur dan susunan organ manusia, misalnya warna kulit, tinggi badan, kapasitas otaknya, dan anggota tubuh lainnya. Sedangkan hasil karya seluruh potensi itu dibahas secara khusus, salah satu yang terdepan: Antropologi Budaya. 1/ Ahimsa, dalam teropong Filsafat Antropologi Dengan demikian, antropologi pun berhak dinyatakan sebagai filsafat yang membahas manusia, yaitu sebuah ilmu yang mempelajari manusia dari aspek keanekaragaman baik fisik maupun kebudayaannya, seperti cara mereka berperilaku, tradisi, norma dan nilai bersama yang dianut, yang semuanya ini akan membedakan antara satu manusia dengan manusia lainnya. Artinya pula, sebagai filsafat, antropologi menjadi studi untuk mempelajari manusia, fenomena yang melingkupinya dan kebudayaan yang dihasilkannya. Masalah jiwa-badan-roh dan apa yang mungkin muncul dari ketiganya, atau sekurang-kurangnya tentang jiwa-badan saja, adalah masalah utama ketika mendiskusikan manusia. Dan ini menjadi lapangan yang luas bagi Filsafat Antropologi. Apakah diskusi tentang manusia (jiwa-badan) itu distingtif, berbeda, sama atau sebuah kesatuan, sejak lama sudah menjadi perbincangan hangat. Bahkan filsuf-filsuf Yunani kuno, seperti Plato, Aristoteles, Sokrates, dll di awal-awal kemunculannya, menjadikan masalah jiwa-badan sebagai masalah kefilsafatan yang serius. Hingga akhirnya, filsuf-filsuf dengan mazhab rasionalis-kritis, semisal Sartre, Descartes, dll juga masih menyoal dengan sengit masalah klasik ini. Pandangan agama juga belum mampu menjadi middle way atas masalah ini secara tuntas. Kehadiran filsuf yang fokus bicara Filsafat Manusia, salah satunya Ponty, juga masih dipersoalkan pemikiran-pemikirannya. Filsafat manusia, dimasa lalu sering berdekatan atau bahkan disebut dengan istilah psikologi filosofis atau psikologi rasional, namun masalah ini tetap dianggap bermasalah karena tampak parsial, hanya membahas satu aspek dari manusia, yaitu jiwa semata. Karenanya, antropologi filosofis menjadi tampak lebih eksak, mengingat yang akan dipelajari manusia secara keseluruhan, tentang jiwa-badan dan hubungannya dengan dunia dan alam.1 Meskipun masalah manusia sudah banyak dituliskan,2 selain dari nama-nama besar di atas, mengulasnya dari Filsafat 1 Louis Leahy. Siapakah Manusia? Yogyakarta: Kanisius, 2001, hlm 15-16. 2 Masalah ini juga sudah dibukukan oleh Soerjanto Poespowardojo dan K. Bertens. Sekitar Manusia. Jakarta: Gramedia, 1985; Michael Polanyi. Kajian tentang Manusia. Yogyakarta: Kanisius, 2001; Drijarkara. Filsafat Manusia. Yogyakarta: Kanisius, 1969. 2/ Ahimsa, dalam teropong Filsafat Antropologi Antropologi tetap masih terasa asing. Bakker (2000) bahkan menganggap kehadiran ilmu-ilmu manusia seperti antropobiologi, sosiologi, psikologi tidak cukup mampu mendalami manusia secara filsafat yang memang sedari awal berangkat dengan pertanyaan kritis untuk mengungkap masalah sampai keakarnya, bahkan secara radikal.3 Meskipun kemudian, Bakker sendiri akhirnya juga mengakui bahwa ilmu-ilmu seperti antropologi salah satunya, tetap memberikan data-data positif yang akan dijadikan filsafat sebagai contoh dan ilustrasi untuk uraian panjang lebarnya. Jadi, ada rangsangan pisikologis yang besar bagi filsafat untuk mempelajari soal-soal tertentu.4 Sedangkan antropologi sebagai satu kajian khusus yang mempelajari manusia, lalu menggambarkannya secara mendalam (thick description), adalah satu cara bagi antropologi memahami kebudayaan yang menjadi wujud dari segala tindakan dan ide manusia. Mereka bertindak, berpikir dan menyadari dirinya dan dengan ini mereka menghasilkan apa yang kita sebut kebudayaan. Melalui pendekatan antropologi, masalah kefilsafatan tentang manusia, penulis menjadikannya sebagai alat untuk menarasikan aneka dan aktivitas manusia, sebagaimana halnya Mahatma Gandhi memahami dirinya sebagai manusia dan tindakan-tindakan yang dihasilkannya. Gerakan moral Ahimsa dapat dijelaskan dari awal kemunculannya dan hasil-hasil yang dicapainya, bahkan ketika India merdeka lepas dari koloni Inggris. Artinya, posisi manusia, dalam hal ini Gandhi, para pengikut dan lingkungannya dapat dilihat dari berbagai bingkai sosial, ekonomi, politik dan budaya, termasuk pengalaman dan alam kesadarannya.5 Dalam antropologi, salah satu metode yang sangat sentral adalah mengamati aktor, atau manusia, sehingga narasi tentangnya dapat ditelusuri bermula dari aktor tersebut. 3 Anton Bakker. Antropologi Metafisik. Yogyakarta: Kanisius, 2000, hlm 13. 4 Ibid., hlm. 135 Clifford Geertz,. The Interpretation of Cultures: Selected Essays. London, Hutchinson & CO Publisher LTD, 1973. (The Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture [1973a]; James P. Spradley. Metode Etnografi. Terjm. Misbah Zulfa Elizabeth dari The Ethnographic Interview , 1979. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007. 3/ Ahimsa, dalam teropong Filsafat Antropologi Bagaimanapun, subjek adalah mereka yang menyadari visi dan dunianya sendiri.6 Serupa dengan ini, Bruner (1986) mengatakan pendekatan antropologi lebih menitikberatkan bagaimana subjek memandang pengalamannya sendiri, termasuk bagaimana mereka berusaha memahami dunia sebagai subjek yang mengalami dan melihatnya dengan perspektif yang ada dalam dirinya sendiri.7 Artinya pula, kesejarahan dari sebuah kebudayaan akan selalu merupakan bahan diskusi yang belum final, dan selalu dalam “proses menjadi” ketika dimensi ruang dan waktu, serta dinamika yang dikandung di dalamnya menjadi wilayah diskusi kebudayaan secara mendalam.8 Cara antropologi, terutama metodologinya itu serta bagaimana cara bekerjanya metode filsafat mengungkap makna, menjadi satu cara untuk membaca ulang apa yang telah dilakukan Gandhi di masa lalu. Konsekuensinya adalah antropologi dalam tema ini tidak mungkin “menjejak bumi” sebagaimana keharusan yang dilakukan antropolog, tetapi terbantu oleh metode filsafat. Bagaimanapun, hubungan antara manusia dengan dunia secara khusus nyata ada dalam kebudayaan. Berbeda dengan binatang yang hanya menjadi bagian dari alam belaka.9 Binatang tidak bertanggung jawab terhadap dunia dan lingkungannya, apalagi kebudayaan. Manusia sebaliknya. Ia menjadi bagian sekaligus bertanggung jawab di dalamnya. Gandhi, dengan segala kesadarannya, terus berproses hingga memiliki kesanggupan memahami dirinya, membangun dimensi sosialnya, dan penghargaannya terhadap alam semesta. Ahimsa yang dijadikan gerakan moral oleh Gandhi adalah ajaran etika dalam agama Hindu. Ditangan Gandhi, Ahimsa adalah cara untuk menginternalisasikan satu sikap etis, bahkan satu budaya seharusnya, dalam memahami diri sebagai bagian 25. 6 Malinowski, B. Argonauts of the Western Pacific. Waveland Press Inc., 1984 (1922), hlm 7 Edward Bruner. Experience and Its Expressionsdalam Bruner (ed) The Anthropology of Experience. Chicago: University of Illinois, 1986. 8 Geertz, op.cit.1973, hlm. 89. 9 Albert Snijders. Antropologi Filsafat. Manusia Paradoks dan Seruan. Yogyakarta: Kanisius, 2004, hlm. 57. 4/ Ahimsa, dalam teropong Filsafat Antropologi tak terpisahkan dari alam. Beberapa bunyi kitab Upanisad bahkan dengan tegas menyatakan bahwa manusia bagian dari Tuhan dan Tuhan secara mikrokosmos berada di alam, tempat manusia hidup. Dengan ini, manusia tidak berhak menyakiti Tuhan yang berada dalam dirinya, juga menyakiti alam sebagai tempat Tuhan bersemayam. Manusia memberikan penghargaan yang mulia atas keberadaan Tuhan dalam dirinya, juga keberadaan Tuhan di alam. Gandhi pada titik itu sangat berhasil menjadikan dirinya (badannya) sebagai “Tuhan” itu sendiri, pandangan yang sama berhasilnya saat Gandhi menyatakan manusia-manusia yang selama ini dianggap liyan, berbeda, bahkan jorok seperti kaum paria, tetap harus mendapat penghargaan. Gandhi berjuang untuk dirinya sendiri, orang lain (sesama) dan dunia luarnya. Ahimsa menjadi meta-ajaran yang secara total dilakukan Gandhi bahkan berhasil menjadi satu bentuk alternatif resolusi menghadapi kekerasan. Pada saat tertentu, Gandhi memisahkan jiwa dan badan, namun saat bersamaan pula menjadi kesatuan teologis untuk menemukan pembebasan. Filsafat Antropologi dalam pemikiran Gandhi tentang Ahimsa menjadi kajian bukan hanya tentang hubungan jiwa-badan semata, tetapi bagaimana manusia membangun relasi dengan dirinya sendiri, orang lain dan alamnya, kebudayaannya. Bakker (1994) mengatakan kebudayaan adalah penciptaan, penertiban dan pengolahan nilai-nilai insani. Artinya, Filsafat Antropologi dapat menjadi alat análisis untuk menjelaskan bagaimana manusia bertindak, berpikir dan berbudaya.10 Apa yang dilakukan Gandhi, baik dari pengakuan orang lain, maupun terutama apa yang dikatakan dan ditulisnya selama hampir 40 tahun menjadi titik sentral untuk diceritakan kembali, salah satunya melalui etnografi. Ahimsa yang menjadi pokok diskusi dalam buku ini adalah ajaran moralitas tertinggi dalam memahami Sang Diri, dan hubungannya dengan seluruh kebudayaannya. Hindu menyebut 1 J.W.M. Bakker. Filsafat Kebudayaan. Yogyakarta: Kanisius, 1994, hlm. 22. 5/ Ahimsa, dalam teropong Filsafat Antropologi adagium ini dengan ahimsa paramo dharma, yaitu “Ahimsa adalah dharma (kebajikan) tertinggi.” Apa yang dilakukan Gandhi hingga akhirnya berhasil menjadikan Ahimsa sebagai “alat” untuk melawan kekerasan, tak bisa dilepaskan dari pengetahuan, pengalaman dan konsistensinya dalam menjalankan Ahimsa. Sudah banyak tokoh atau pergerakan yang gagal karena nirkonsistensi ini. Gandhi menjalankan Ahimsa tidak tiba-tiba. Ia mendapatkan begitu banyak penderitaan dan pengorbanan hingga saat kemenangan tiba, ia juga tidak mengambil hadiahnya. Berkat Gandhi dan dengan moralitas Ahimsa, ia berhasil mengkonstruksi sebuah humanisasi dari “dunia alam” menjadi “dunia budaya.” Gandhi, sekali lagi, berhasil memulai dari dirinya sebagai manusia utuh, dan memandang manusia lain dan dunia sama utuhnya. Ahimsa sebagai moralitas tertinggi hadir untuk tidak saling menegasi karena keduanya sama. Tidak saling menyakiti dan melukai adalah moralitas tertinggi itu. Apa yang diperlihatkan Gandhi dalam sejarah pembebasan India tanpa darah, menjadi tanggung jawabnya sebagai manusia, representasi dari kemampuan mengenali dirinya sendiri, lalu memperlakukan hal yang persis sama untuk orang lain. Dari pengenalan dirinya secara mendalam ini, Gandhi mengatur dengan baik sikap etis dalam hidupnya [*] 6/ Ahimsa, dalam teropong Filsafat Antropologi “…Peradaban sekarang berada dalam genggaman kekerasan yang semakin meningkat…Tindakan tanpa kekerasan masih berupa tetesan dibandingkan dengan gelombang pasang kekerasan yang menyapu dunia. Tetapi…militerisme dan senjata nuklir adalah tonggak-tonggak berdarah yang menandakan jaman yang sedang mengalami kepunahan…” (G. Ramachandran, Sekretaris Yayasan Perdamaian Gandhi di India) 7/ Ahimsa, dalam teropong Filsafat Antropologi 8/ Ahimsa, dalam teropong Filsafat Antropologi BAGIAN SATU: Mengapa Ahimsa? ...................................................................................................................................................................... Dewasa ini, tindakan kekerasan hampir selalu menjadi alat untuk memperjuangkan segala macam bentuk ideologi, apakah itu soal kemerdekaan, kebenaran, kedamaian, keadilan atau pun sekadar cita-cita. Seolah kekerasan adalah jalan paling sahih, atau mungkin satu-satunya, untuk menemukan semua ambisi itu. Ada semacam keyakinan bahwa situasi dapat diubah atau nilai hakiki serta martabat manusia dapat ditegakkan hanya melalui tindakan kekerasan dan unjuk kekuatan. Namun, tindakan kekerasan, dalam bentuk apa pun, termasuk yang bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) yang melibatkan individu, terlebih kelompok atau negara akan selalu mendapat perlawanan. Misalnya, ketika sebuah negara menggalang kekuatan melalui kemutakhiran senjata, maka di lain pihak selalu akan ada kekuatan yang berusaha untuk “mengalahkannya,” bahkan harus melalui kekerasan baru. Tidak dapat dihindari bahwa segala bentuk saling “mengalahkan” ini dapat saja mengambil wujud peperangan, konflik terbuka, anarkhi atau teror. Kontra strategi dalam sebuah pertarungan tidak hanya mewujud dalam hard war, tapi juga soft war, sebagaimana pertarungan dalam dunia wacana dan media sosial (medsos), seperti akhir-akhir ini. Penyadapan yang dilakukan Amerika Serikat kepada beberapa negara dan tokoh penting dunia pada 2013 silam, atau penyadapan Australia kepada salah satunya Presiden Ke 6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pada 2013 menjadi contoh aktual.1 Segera setelah penyadapan ini dilawan 1 Dalam dokumen yang dibocorkan whistleblower Edward Snowden, mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional (NSA) Amerika Serikat, Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) disadap Australia. Berdasarkan laporan yang dimuat The Guardian dan ABC, Senin 18 November 2013, disebutkan SBY bersama 9 jajaran petinggi negara, termasuk Wakil Presiden Boediono dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menjadi target penyadapan pada 2009 (http://global.liputan6.com/read/748895/ snowden-ponsel-sby-disadap-australia diakses tanggal 29 Desember 2016). 9/ Ahimsa, dalam teropong Filsafat Antropologi dengan pemutakhiran sistem keamanan teknologi informasi. Kontra strategi seperti ini kadang menjadi drama yang menarik, bahkan mungkin menguntungkan bagi beberapa pihak, tetapi celakanya tidak serta merta mengakhiri arena pertarungan yang sesungguhnya. Banyak resep yang ditawarkan para ahli untuk mengatasi segala macam bentuk tungkai pangkai, tepatnya konspirasi seperti di atas, entah konflik, perang dan kekerasan lainnya, terutama peperangan sebagai salah satu bentuk nyata implikasi terbesar dari tindakan kekerasan. Tercatat salah satu nama ahli itu adalah Johan Galtung, pakar studi perdamaian paling terkemuka yang melahirkan gagasan tentang perdamaian positif dan perdamaian negatif, meski kemudian Galtung sendiri tampaknya gagal mempraktekkannya dalam kondisi-kondisi tertentu. Begitu juga apa yang disebut Just War (perang adil) yang mengadopsi pemikiran St. Augustinus tentang pengaturan perang yang adil dengan membatasi perang itu sendiri. Misalnya kapan dan di saat yang mana perang boleh tidaknya dilakukan.2 Laiknya Bharatayudha yang dianggap sebagai salah satu perang terbaik yang memiliki peraturan khusus.3 Belakangan muncul pola baru untuk menangani kekerasan yang banyak dipakai oleh lembaga atau negara, yaitu melalui kekerasan itu sendiri dan penghimpunan kekuatan di dalamnya, serta penggunaan hukum-hukum yang ketat. Jika keberhasilan kedua pola ini hanya didasarkan pada hasil akhir, mungkin dapat disebut berhasil, tapi hanya bersifat sementara. Mengapa? Karena kedua pola ini pun dapat “tergelincir” dengan hilangnya makna dan nilai moral paling dasar manusia, yaitu dehumanisasi. Keduanya sama-sama jatuh pada adagium “kuasa manusia atas 2 Lihat Dan Smith. “Legitimacy, Justice and Preventive Intervention “ dalam Peter Wallenstein (ed.), Preventing Violent Conflict: Past Record and Future Challenge. Stockhlm: Elanders Gotab, 1998, hlm. 268-270. 3 Dalam Mahabharata, perang akan dimulai pada pagi hari setelah semua prajurit melaksanakan doa bersama, lalu ditandai dengan tiupan Sangkakala. Menjelang malam, perang harus dihentikan. Yang terluka harus dirawat bersama, para prajurit yang berseberangan masih bisa bercengkrama. Begitu juga, jika ada lawan yang sudah kalah dan menyerah, mereka tidak boleh dibunuh. 10/ Ahimsa, dalam teropong Filsafat Antropologi manusia yang lain,” yang justru berpotensi melahirkan kekerasan baru. Dalam upaya mereduksi kekerasan seperti inilah, Mahatma Gandhi – selanjutnya hanya disebut Gandhi saja – menghadirkan sebuah gagasan alternatif dengan justru melakukan tindakan anti-kekerasan, yang secara khusus dinamakan Ahimsa. Secara harafiah kata Ahimsa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu bentukan dari urat kata “a” yang berarti tidak, tanpa (non), sedangkan “himsa” berarti membunuh, melukai, menyakiti atau melakukan tindakan kekerasan kepada semua makhluk hidup. Jadi Ahimsa berarti tidak menyakiti, melukai, membunuh, bertindak keras, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Dalam ajaran agama Hindu, Ahimsa menjadi salah satu pedoman penting untuk pengendalian diri, keinginan dan nafsu berlebihan. Tanpa kekerasan, itulah gaya perjuangan Gandhi yang mungkin bagi kaum pragmatisme akan terasa sangat idealistik dan tidak populer, tetapi di tangan Gandhi ternyata telah berhasil mendapatkan kemenangan. Keberhasilan dan kemenangan gerakan tanpa kekerasan disebutnya sebagai kemenangan kemanusiaan atas segala ketidakadilan dan penindasan terhadap nilai dasar manusia, seperti penjajahan, diskriminasi dan segala bentuk kekerasan lainnya. Pendek kata, Ahimsa dirumuskan sebagai gerakan nonkekerasan (non-violence). Gandhi berkeyakinan bahwa Ahimsa adalah struktur kodratiah manusia dan sebagai jalan untuk menemukan kebenaran. Dalam Ahimsalah segala gerak, kata-kata dan pikiran manusia terpusat dan terkendalikan. Karenanya, kalau manusia mau bertindak secara manusiawi, maka ia harus melaksanakan Ahimsa. Keharusan seperti ini sebenarnya tidak datang dari luar atau dari otoritas tertentu melainkan muncul dari dalam struktur manusia yang bermoral, berbudaya, beradab dan tentu saja bermartabat. Apa yang dirancang Gandhi melalui strategi Ahimsa adalah sebuah esensi pergerakan yang mutual gain. Esensi ini adalah sebuah kondisi sosial untuk menuju ke perubahan yang baik. Gandhi melihat bahwa kekerasan atarmanusia merupakan 11/ Ahimsa, dalam teropong Filsafat Antropologi kondisi yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan manusia. Meski demikian, tindakan kekerasan dapat dianggap sebagai tindakan yang salah dalam upaya mencari solusi perdamaian di antara pihak-pihak yang berkonfrontasi. Artinya, kekerasan merupakan cara yang tidak efektif untuk mencapai tujuan. Kekerasan dalam bentuk apapun merupakan tindakan irasional bagi perdamaian. Gandhi sendiri melihat bahwa kekerasan muncul melalui struktur dan kekerasan langsung yang dilakukan karena adanya pelaku, ada actor. Sejalan dengan hal tersebut, Jack D. Douglas dan Frances Chaput Waksler juga menyatakan bahwa kekerasan adalah gambaran perilaku dari yang terbuka (overt) maupun tertutup (covert). Masing-masing dapat menyerang (offensive) atau bertahan (deffensive).4 Masing-masing pula dapat berpotensi besar melahirkan kekerasan. Begitu seterusnya, eskalatif. Menariknya, apakah model gerakan Gandhi dalam menghadapi segala bentuk kekerasan yang terjadi masih relevan untuk dipraktekkan, atau paling tidak dapat menjadi pilihan lain dalam menghadapi berbagai bentuk kekerasan yang telah menyerang kaidah-kaidah dasar kehidupan dewasa ini? Ini adalah pertanyaan awal dari banyak pertanyaan yang akan muncul kemudian. Pertanyaan berikutnya, apakah Ahimsa dapat menjadi sebuah anti-tesa bagi kekerasan untuk menemukan sintesa, yaitu kedamaian hidup. Atau bagaimana posisi Ahimsa dalam wacana global dan di era new age belakangan ini? Bukan bermaksud menjadi naif atau membuat simplitis dari pertanyaan berat di atas, menurut hemat penulis, Gandhi telah memberikan formula jitu bagaimana menghadapi dan menyelesaikan sebuah konflik. Menurut Gandhi, cara terbaik untuk menyelesaikan setiap konflik adalah cinta kasih dan menerima semua makhluk sebagai bagian dari diri. Cinta kasih bukan suatu sifat yang pasif, melainkan aktif, diperlihatkan dalam usaha dan perjuangan. Maka, Ahimsa bukan pula sifat yang pasif, diam, dan negatif, melainkan sebuah daya kekuatan dari kebenaran cinta kasih yang diperlihatkan dalam tindakan. Ahimsa 4 Thomas Santoso. Teori-Teori Kekerasan. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 11. 12/ Ahimsa, dalam teropong Filsafat Antropologi mendorong untuk aktif menyelesaikan kekerasan. Sekali lagi, bukan fatalis. Membaca persoalan di atas, maka setidaknya ada dua alasan penting mengapa Ahimsa sebagai gerakan moral dalam pemikiran Gandhi menjadi tema buku ini, yaitu pertama, karena konsep ini mengajarkan kepada semua orang – termasuk semua penganut agama – untuk hidup damai dengan tanpa kekerasan, dan selalu bertumpu penuh pada kebenaran Tuhan. Ahimsa menjadi ajaran yang secara esensial menyiratkan kesadaran untuk hidup dalam kedamaian, sebuah kesadaran yang dilandasi oleh nilai-nilai kebaikan tentang kehidupan. Secara alamiah, tidak ada manusia yang tidak ingin damai dan jauh dari kekerasan. Alasan yang lain adalah hingga saat ini kita masih dihadapkan pada berbagai problema konflik yang di dalamnya begitu banyak memuat kekerasan. Kini bahkan semakin kompleks, baik kekerasan terhadap sesama maupun kepada makhluk hidup lainnya. Konflik sosial-politik yang melibatkan negara dan warga terjadi juga sebagai akibat dari hal ini. Penulis ingin Ahimsa dapat menjadi gerakan moral bagi penyelesaian berbagai konflik itu. Sebab dengan Ahimsa, sesungguhnya kita dapat memberikan penghormatan kepada semua bentuk kehidupan. Ini adalah sebuah pandangan yang telah memiliki sejarah panjang dan bisa diartikan bahwa setiap orang, baik perempuan maupun laki-laki, harus menghindari kejahatan dengan hanya melakukan perbuatan-perbuatan baik di dunia. Menurut penulis, Ahimsa bukan hanya sekadar tingkatan tidak melakukan penyerangan secara negatif, tetapi juga tingkatan cinta kasih yang positif, berbuat baik bahkan kepada penjahat sekalipun. Sebagaimana keyakinan Gandhi, penulis juga meyakini bahwa hanya cinta atau non-kekerasan yang akan menaklukkan kejahatan, di mana pun dia berada – dalam diri orang-orang atau tatanan hukum, agama, politik, dalam masyarakat atau pemerintahan sekalipun. Fenomena perang atau friksi dengan kontak fisik dan sejenisnya adalah bentuk-bentuk kekerasan yang sering dijadikan 13/ Ahimsa, dalam teropong Filsafat Antropologi alasan untuk menyelesaikan konflik. Tetapi ternyata perlawanan terhadap kekerasan dengan cara-cara kekerasan justru mengundang kekerasan yang lebih besar. Pendekatan dengan cara seperti ini seringkali gagal. Kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak, menyelesaikan kekerasan dengan kekerasan akan terlihat kuno saat etika global tanpa kekerasan semakin deras menguat. Kekerasan tidak dapat di atasi hanya dengan kekerasan melainkan dengan sikap tanpa kekerasan. Kedua, alasan dipilihnya Mahatma Gandhi (1869-1948) karena Gandhi adalah tokoh universal yang pemikiran dan pandangannya dapat diterima hampir oleh semua orang, termasuk penganut non-Hindu. Ia diberi nama Mahatma karena keluhuran dan kemuliaan jiwanya.5 Tidak aneh kalau tokoh yang diwajahnya selalu tampak tersenyum ini seolah menjadi milik semua orang, milik publik. Sulit menjelaskan personalitas seorang Gandhi. Orang Islam menyebutnya Muslim dan orang Nasrani menyebutnya Kristen. Bahkan di atas meja tempat ia berefleksi, tertata rapi kitab Bhagavad-Gita, Al-Qur’an dan Injil. Keragaman pribadinya memang telah terbentuk oleh kecintaannya kepada persoalan kemanusiaan yang melintasi perbedaan agama, suku, ras, status bahkan ruang dan waktu. Tidak aneh pula ketika berada di Johannesburg, Afrika Selatan ia bahkan dijuluki “Raja Umat Hindu dan Muslim.” Dibalik kelembutannya, tersimpan energi besar jika menyaksikan kekerasan. Gandhi, ia adalah “manusia kecil bernyali besar.” Demikian juga perjuangan, gerakan dan kehidupan Gandhi yang tanpa kekerasan telah memberi inspirasi bagi banyak orang, terutama tokoh-tokoh anti kekerasan yang muncul kemudian, seperti Martin Luther King Jr., Dalai Lama, Nelson Mandela, Aung San Suu Kyi hingga Cesar Chavez. Pengajaran Gandhi terhadap kehidupan tokoh-tokoh ini membawanya pada keyakinan atas perjuangan dengan cinta kasih dan tanpa kekerasan untuk membebaskan umat manusia.6 5 Mahatma juga berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu “maha“ yang berarti besar, agung, suci, luhur dan “atma“ artinya jiwa, roh, atau dalam konteks pembahasan ini lebih menunjuk kepada pribadi seseorang. 6 Stanley Wolpert. Mahatma Gandhi, sang penakluk kekerasan, hidupnya dan ajarannya. terjm. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. xii. 14/ Ahimsa, dalam teropong Filsafat Antropologi Bahkan Solarz, seorang anggota Kongres Amerika Serikat mengatakan bahwa pengambilalihan kekuasaan dari tangan Ferdinand Marcos oleh Corazon Aquino pada 22-25 Februari 1986 melalui sebuah revolusi damai, yang kemudian dikenal dengan people power, diyakini telah “mengadopsi” gerakan nonkekerasan ala Gandhi. Hal yang sama terjadi juga pada gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat dan gerakan solidaritas di Polandia. Sementara ilmuwan terkemuka dunia, Albert Einstein memujinya sebagai manusia termulia yang pernah dilahirkan di muka bumi, lalu menyamakannya dengan Sidharta Gautama, pendiri agama Buddha. Universalitas pemikiran Gandhi dapat juga dilihat dalam bidang hidup keagamaannya, meskipun ia sendiri berakar kuat dalam tradisi besar agama Hindu, ia mengembangkan perspektif keagamaan yang bersifat moral dengan mendalam. Dari sudut pandang ini, ia melihat konvergensi antara agama-agama dan menyiarkan keselarasan antaragama, yakni umat beriman yang saling mendorong untuk mencari kebenaran dengan tindakan tanpa kekerasan. Sedangkan pada tingkat sosial, Gandhi mendukung keselarasan komunal, khususnya antara orang-orang Hindu dan Muslim berdasarkan toleransi timbal balik, pemahaman satu sama lain dan kerjasama demi kesejahteraan semua orang. Dengan demikian, ketokohan seorang Gandhi dapat menjadi bukti bahwa perbedaan antarpandangan agama sesungguhnya dapat disatukan dalam sebuah pandangan hidup yang sama, kekal dan abadi. Bahkan salah satu pemikiran Gandhi yang sangat berdimensi humanis-teologis adalah dengan mengajak seluruh umat manusia untuk selalu menjalankan kebenaran agama; kebenaran adalah kebaikan tertinggi. “Kebenaran adalah agama saya dan Ahimsa adalah satu-satunya jalan untuk mengejewan-tahkannya”, katanya suatu ketika. Dari pernyataan ini muncul slogan emas Gandhi: “Tuhan adalah kebenaran dan kebenaran adalah Tuhan.” Tuhan disamakan sebagai hakekat kenyataan terakhir. Pandangan Gandhi ini sangat terinspirasi dari cara Sang Buddha memandang kebenaran yang semestinya tidak hanya 15/ Ahimsa, dalam teropong Filsafat Antropologi diterima begitu saja, lebih-lebih hanya mengagungkan Tuhan dengan sebuah simbolik. “Datang dan lihat, ehi passika,” seru Sang Buddha.7 Gandhi dilihat tidak hanya sebagai tokoh pergerakan yang berusaha membebaskan bangsanya dari imperialisme Inggris, tetapi juga seorang yang mempunyai integritas tinggi sebagai seorang spiritualis. Dengan ajaran Ahimsa, ia ingin menjembatani segala perbedaan manusia melalui ajaran-ajaran cinta kasih dan tidak melakukan kekerasan kepada seluruh makhluk hidup. Ahimsa, dengan demikian menjadi ajaran universal yang secara esensial dapat menjadi gerakan moral dalam segala aspek kehidupan manusia. Bagi Gandhi, Ahimsa adalah senjata dari potensi yang tak tertandingi. Ia adalah kebaikan tertinggi (summum bonum) dari kehidupan. Bila tindakan seseorang didorong oleh cinta kepada makhluk di alam semesta, tindakan itu dapat menunjang kebaikan tertinggi. Dengan demikian, cinta adalah kebajikan utama. Dalam hal ini Gandhi menggunakan kata Ahimsa dan memperluas artinya sehingga Ahimsa bukan hanya menahan diri dari melukai orang lain. Substansi Ahimsa sebagai gerakan moral sudah dimulai dari pernyataan mendasar ini. Setidaknya ada tiga pertanyaan penting sebagai Tema Pokok yang dapat diajukan di sini, yaitu pertama, apakah Ahimsa sebagai gerakan moral cukup efektif untuk menumbuhkan kesadaran etis? Pertanyaan ini menjadi penting karena sebagai gerakan moral, apakah Ahimsa cukup kuat menjadi lapangan bagi filsafat moral dalam upaya penumbuhan kesadaran etis, yang kalau tidak hati-hati dapat jatuh ke dalam pandangan agama semata, meskipun dalam keadaan tertentu, kesadaran moral kita biasanya dilekatkan pada gerakan moral dalam agama. Namun Ahimsa di sini hendak dilihat dalam tataran moral di mana kekuatan moral agama dan sifat rasional manusia menjadi kesatuan pandangan, khususnya dalam melihat persoalan kekerasan. 7 Ngakan Made Madrasuta dan Sang Ayu Putu Renny. Gandhi dalam Dialog Hindu-Kristen. terjm. Surabaya: Paramita, 2002, hlm. 108. 16/ Ahimsa, dalam teropong Filsafat Antropologi Setelah penjernihan ini, baru kemudian kita akan melihat sejauhmana Ahimsa dapat menjadi landasan berpikir untuk melakukan praksisisme, seperti pengangkatan kembali (emansipasi) sifat dasar dan nilai fundamental manusia, yaitu martabat dan cinta kasih manusia. Kedua, apakah gerakan moral Ahimsa dapat menjadi sebuah media atau alat bagi pemecahan konflik sosial-politik? Apa yang ingin dicapai melalui perumusan ini? Penulis ingin mendudukkan posisi yang jelas bagi gerakan moral Ahimsa di tengah-tengah berbagai konflik dan kekerasan dan cara-cara yang telah dipergunakan untuk menghadapinya. Sehingga pencapaian kita adalah Ahimsa dapat menjadi resolusi konflik dan anti-tesa terhadap kekerasan untuk kemudian menemukan kedamaian sebagai sintesanya. Struktur ini jelas akan mengikuti pemikiran dialektika Hegel. Ketiga, pertanyaan ketiga adalah apakah prinsip-prinsip moral yang dikembangkan melalui Ahimsa masih cukup berpengaruh terhadap dunia, dan sejauhmanakah relevansinya dengan kehidupan sekarang? Menurut penulis rumusan ini harus dikemukakan untuk melihat sejauhmanakah kemanfaatan metode tidak populer Ahimsa dalam kehidupan sekarang. Sebab bagaimanapun, tulisan tentang Ahimsa setidaknya dapat memenuhi prediksi kritis yang terkandung di dalamnya. Jawaban atas pertanyaan ini akan dapat menjelaskan apakah Ahimsa dapat berpengaruh dalam bidang politik, pemerintahan dan kemasyarakatan. Latar belakang lahirnya konsep moral Ahimsa sepenuhnya tidak dapat dilepaskan dari begitu banyak kekerasan atau bahkan peperangan yang pernah terjadi, bahkan sejak dari jaman Yunani Kuno di mana telah berkembang mitos adanya Dewi Perdamaian (Irene).8 Namun, semenjak berakhirnya Perang Dunia II, yang berarti penjajahan dalam bentuk perang atas satu bangsa kepada 8 J.G. Starke, Q.C., An Introduction to the Science of Peace(Irenology). Leiden: A.W. Sitjhoff ’s Uitgeversmaatscappij N.V., 1968, hlm. 15. 17/ Ahimsa, dalam teropong Filsafat Antropologi bangsa lain sudah tidak mendapat tempat lagi, pencarian akan perdamaian masih dan akan terus dilakukan. Hal ini didasarkan atas masih banyaknya berbagai tindakan kekerasan, termasuk kekerasan global, macam teror yang masih terus terjadi. Bahkan perang dingin saat dua blok Barat-Timur rontok, belum menghentikan situasi memanas yang setiap waktu bisa meledak menjadi konflik. Begitu juga geopolitik yang melanda beberapa negara, terutama kawasan Timur Tengah yang sempat dikenal dengan Arab Spring masih terus bergejolak hingga kini. Belum lagi konflik-konflik bernuansa etnis, salah satu yang paling mengemuka saat ini adalah dugaan kekerasan yang dilakukan militer Myanmar terhadap etnis Rohingnya. Kenyataan ini pula yang mendorong lahirnya studi-studi khusus yang mencoba memecahkan dan mencari perdamaian dalam konflik. Salah satu ilmu itu adalah polemologi yang bergerak atas adanya polemik antara perdamaian dan konflik. Studi tentang perdamaian secara jujur harus diakui ternyata juga belum sepenuhnya mampu menjawab berbagai permasalahan kekerasan dan perang. Bahkan kebijakan publik tentang persoalan kekerasan yang muncul belakangan juga menjadi agak paradoks dan cenderung hanya dibingkai oleh dua pola utama, yaitu “perdamaian melalui kekerasan” dan “kontrol hukum.” Kegagalan dari cara-cara seperti ini menginspirasi keharusan munculnya teori liyan Ahimsa sebagai formula bagi pemecahan konflik, solusi perdamaian atau pun sebagai gerakan moral untuk menjamin upaya-upaya memanusiakan manusia berdasarkan sifat hakiki yang telah dimilikinya. Pola Ahimsa ala Gandhi ini, masih mungkin menjadi bahan perdebatan. Meski kemudian pola ini akhirnya diakui sebagai pola alternatif yang dianggap paling efektif dan dapat dikategorikan sebagai pemikiran religius-ilmiah. Gandhi sendiri sesungguhnya banyak mengadopsi filsafat India yang tercerap ke dalam kitab Bhagawad-Gita, Upanisad, Aliran Jaina, Filsafat Samkhya serta besarnya pengaruh ajaran Buddha. Gandhi juga sangat diinspirasi 18/ Ahimsa, dalam teropong Filsafat Antropologi oleh penulis Rusia Leo Tolstoy melalui karyanya The Kingdom of God is Within You.9 Setidaknya kelahiran konsep Ahimsa sangat didorong oleh pengalaman pribadi Gandhi sejak awal perjuangannya di Afrika Selatan saat ia menggagas gerakan revolusioner bernama Satyagraha, gerakan yang sepenuhnya mendasarkan diri pada kebenaran Tuhan, atau komitmen dan kecintaan kepada kebenaran. Melalui Satyagraha-Ahimsa ini, Gandhi memberikan gambaran yang komprehensif terhadap fakta-fakta kekerasan yang dihadapi dengan cara-cara anti-kekerasan untuk mencapai tujuan. Kecintaan kepada kebenaran merupakan alat bagi pemahaman atas konflik yang terjadi dan dimensi-dimensi yang terdapat di dalamnya. Dimensi-dimensi itu adalah manusia sebagai pelaku kekerasan harus juga dilihat sebagai sebuah keadaan yang riil, ada. Pergerakan Ahimsa ini kemudian tumbuh menjadi sebuah usaha untuk melakukan perubahan sosial evolusioner yang dapat dijadikan sebagai alternatif perubahan radikal yang ada dalam sebuah gerakan revolusioner. Gerakan alternatif Ahimsa telah membedakan Gandhi dengan gerakan revolusioner proletar, salah satu yang termasyur Karl Marx, maupun gerakan revolusi ala Lenin, Stalin dll. Dengan demikian, konsepsi Ahimsa secara kritis dapat ditinjau melalui refleksi filsafat, terutama Metafisika, dan tentu Filsafat Antropologi. Ahimsa telah memberikan ruang yang sangat luas terhadap upaya-upaya metafisis dalam melihat fenomena-fenomena manusia dalam kesejatiannya sebagai manusia yang senantiasa berada dalam jaring kosmologi, psikologi dan teologi. Begitupun Ahimsa dapat ditinjau dan menjadi lapangan luas bagi Filsafat Antropologi atau Filsafat Manusia, terutama pandangan Ahimsa terhadap badan, jiwa dan keterkaitan keduanya, serta kesalingterjalinan antarmanusia dengan alam dan dunianya [*] 9 Terhadap karya Tolstoy ini, Gandhi mengaguminya dengan mengatakan: “ Buku ini meninggalkan kesan yang tidak bisa hilang…“ Pada bagian lain, Gandhi juga mengagumi pemikiran independen, moralitas yang hebat, dan kejujuran Tolstoy. Kekaguman yang besar ini bahkan diabadikannya ketika ia membangun Ashramnya yang kedua, dengan nama “Taman Tolstoy.” Lihat Stanley Wolpert, op.cit ., hlm 77. 19/ Ahimsa, dalam teropong Filsafat Antropologi BAGIAN TUJUH: Simpulan ...................................................................................................................................................................... Mahatma Gandhi, sebagaimana telah dipaparkan pada bagianbagian terdahulu, adalah orang yang paling gigih memperjuangkan hak, harkat dan martabat sesama manusia, maupun negara. Ia memperoleh keberhasilan dari perjuangannya justru dengan tindakan yang tidak populer, yaitu melawan dengan tanpa kekerasan. Tindakan ini kemudian lebih dikenal dengan Ahimsa. Sesungguhnya, Ahimsa bukanlah satu-satunya gagasan yang pernah dikembangkannya, namun gagasan lainnya, seperti Satyagraha, Svaraj, Sarvodaya dan Svadesi seolah disintesakannya menjadikan satu gerakan moral yang didasari atas prinsip-prinsip kekuatan jiwa dalam memegang kebenaran dan kekuatan cinta kasih untuk semua orang. Dalam Ahimsa kita menemukan akumulasi dari nilai Satyagraha, Svaraj, Sarvodaya dan Svadesi. Awalnya, gerakan moral Ahimsa memang bermula dari gerakan Satyagraha yang sukses di Afrika Selatan, terutama saat Inggris menjajah dan menindas dengan keji warga kulit hitam Asia (India). Pengaruh besar dari situasi sosial-politik, dan juga pengalaman empiriknya atas diskriminasi rasial, berlanjut hingga ke India saat ia membebaskan bangsanya sendiri dari imperialisme Inggris, dan juga sedikit keberhasilannya dalam mendamaikan konflik-konflik agama yang terjadi. Inilah daftar panjang kemenangan tindakan nonkekerasan terhadap kekerasan. Sebagai sebuah konsep, lalu akhirnya menjadi gerakan moral yang aktif, Ahimsa banyak dilatarbelakangi oleh berbagai varian pemikiran yang terutama bersumber dari akar tradisi Gandhi sendiri sebagai seorang penganut taat agama dan kearifan timur lainnya (terutama Filsafat India). Gandhi berhasil meramu keanekaan pengetahuan dan pengalamanya untuk menghasilkan kepribadian moderat dan universal. Ia menjadi semakin humanis melalui perjumpaan batinnya dengan penganut banyak agama. Tak heran, visi besarnya tentang gerakan non-kekerasan beralaskan religiusitas. Gandhi memandang adanya kenyataan 155/ Ahimsa, dalam teropong Filsafat Antropologi yang sama antara satu manusia dengan manusia lain karena adanya jiwa yang sama, dengan sumber utama dari Tuhan. Ia sekaligus menjawab keraguan bahwa transformasi pikirannya berawal dari bagamana caranya memahami jiwa-badan, lalu memandangnya utuh. Jikapun masing-masing manusia tampak berbeda, itu semata karena badannya, materialnya. Ahimsa sebagai suatu refleksi kefilsafatan menjadi medan luas untuk dikaji dari pandangan Metafisika, dan terutama Filsafat Antropologi. Tinjauan Metafisika menyimpulkan bahwa Ahimsa dengan prinsip-prinsip dasar non-kekerasan terhadap kosmis, makhluk hidup (khususnya manusia) dan pengakuan terhadap Tuhan sebagai kebenaran dan kenyataan terakhir. Pandangan ini seturut dengan kajian Metafisika itu sendiri, terutama apa yang telah dilakukan Christian Wolff mengenai kajian kosmologi, psikologi dan teologi. Hanya saja, pandangan Gandhi tentang jiwa melebihi hakekat dari badan. Artinya, badan hanya dipandang sebagai penopang keberlangsungan jiwa yang tetap hidup dan abadi. Sementara tinjauan Filsafat Antropologi lebih melihat Ahimsa sebagai sebuah unifikasi jiwa-badan yang darinya memunculkan sikap untuk membangun keterjalinan antarmanusia, dan bagaimana manusia membudaya dengan dirinya sebagai “Aku,” orang lain dan dunia sekitarnya. Dalam hal ini, Gandhi melihat bahwa manusia harus mendapat penghargaan utuh sebagai manusia yang mempunyai kesalingtergantungan dengan sesamanya. Manusia sebagai makhluk yang rasional, tentu juga adalah makhluk yang dapat menerima sesamanya sebagai bagian dari dirinya sendiri. Pandangan Gandhi seperti ini sepaham dengan para pemikir, seperti Martin Buber, Gabriel Marcel, Emmnuel Levinas dan Romano Guardini, namun sedikit berbeda dengan Soren Kierkegaard, Martin Heidegger atau Jean-Paul Sartre yang memandang negatif hubungan antarmanusia. Unifikasi badan-jiwa dari Gandhi seturut pula dengan persfektif antropologi, terutama Levi-Strauss, sesungguhnya tidak ada lagi kategori tentang pikiran dan zat. Struktur itu ada pada mind sekaligus pada matter. 156/ Ahimsa, dalam teropong Filsafat Antropologi Lalu, sebagai gerakan moral, Ahimsa secara lebih dalam dapat dipandang sebagai faktor yang mampu membangkitkan sifat dasar paling ideal manusia, yaitu cinta kasih. Ini berarti, Ahimsa dapat juga menjadi satu metode pembangkitan kembali (emansipasi) nilai fundamental dalam diri manusia. Ahimsa juga menjadi pendorong bagaimana kita mesti mampu memberikan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, karena sikap ini juga adalah bentuk kesadaran moral paling dasar. Ahimsa sebagai gerakan moral jelas adalah cara paling baik dalam mempraktekkan sikap dan kesadaran etis kita dalam kehidupan. Lebih jauh lagi, Ahimsa dapat menjadi alat untuk memecahkan konflik, menjadi anti-tesa terhadap segala bentuk kekerasan yang menyerang kaidah-kaidah dasar manusia, meski alasan lahirnya kekerasan dan konflik sangat beragam. Richard Dawkins misalnya, menyebut kekerasan ada karena gen egois yang secara hakiki ada dalam diri manusia yang pada saat-saat tertentu memunculkan agresivitas manusia dengan mengambil bentuk kekerasan. Lain halnya dengan Johan Galtung, seorang Gandhian, yang menyebutkan bahwa kekerasan tidak hanya bersumber pada genetis-biologis, tetapi juga berasal dari interaksi antarmanusia yang tidak seimbang satu dengan yang lainnya. Studi tentang ini sudah semakin banyak dilakukan. Namun, kekerasan dan konflik sesuatu yang nyata ada dan terus berlangsung. Anti-tesa Ahimsa yang ditawarkan Gandhi tentu bermuara kepada upaya pencapaian kedamaian, meskipun upaya ini tidak mudah karena masih ada pola-pola lain yang lebih dominan dipakai orang untuk menyelesaikan kekerasan. Berbeda dengan metode yang sudah lumrah ada, Ahimsa telah menunjukkan bahwa pola-pola lain, seperti penghimpunan kekuatan dan penggunaan hukum rimba sungguh-sungguh dalam waktu tertentu sering kehilangan makna dan nilainya. Dengan gerakan moral Ahimsa, Gandhi telah memberikan contoh terbaik yang diwariskannya kepada dunia. Warisan ini telah banyak diadopsi para pejuang hak-hak kemanusiaan bagi keselarasan dunia tanpa kekerasan. Begitu pula wacana global yang berkembang akhir-akhir ini banyak diinspirasi oleh substansi 157/ Ahimsa, dalam teropong Filsafat Antropologi Ahimsa terhadap segala bentuk kekerasan disegala aspek kehidupan. Nilai dan hakikat Ahimsa secara implisit saat ini telah mulai merasuk dalam ke wilayah politik, agama dan kehidupan bermasyarakat. Namun, gerakan moral Ahimsa juga menyisakan beberapa pertanyaan yang secara kritis, terutama keberpihakan Gandhi pada fungsi jiwa dari pada tubuh, padahal beberapa pemikir, salah satunya yang terkemuka, Maurice Merleau-Ponty telah banyak membuktikan bahwa tubuh juga mempunyai peran yang sama terhadap jiwa, karena melalui tubuh, jiwa bersentuhan. Lalu, pandangan Gandhi tentang kesalingterjalinan juga masih dianggap terlalu positif karena boleh jadi manusia akan menemukan kebermaknaan dirinya sebagai manusia dengan justru melakukan isolasi diri. Di sini, pandangan Gandhi sangat dekat dengan pengaruh religius dan aspek moral yang memengaruhinya. Begitu juga, Ahimsa dianggap masuk ke wilayah bayang-bayang utopia, mengingat lintasan sejarah yang dihadapi Gandhi berbeda dengan konteks jaman hari ini. Sebagai akhir dari tulisan ini, penulis dalam hal tertentu, mungkin sependapat dengan Gandhi bahwa memanusiakan manusia melalui gerakan moral Ahimsa yang terlibat dalam sebuah konflik dan atau tindakan kekerasan masih relevan untuk dipakai sebagai senjata paling damai, paling humanis, karena telah begitu banyak bukti: konflik, perang dan kekerasan yang dihadapi atau dilawan dengan kekerasan justru melahirkan kekerasan baru yang menelan banyak korban yang tidak perlu. Menyelesaikan kekerasan dengan kekerasan adalah saham bagi munculnya kekerasan baru yang mungkin lebih kejam dari kekerasan sebelumnya. Ahimsa juga mengajak kita untuk kembali menjernihkan pikiran, perkataan dan perbuatan sebelum melakukan tindakan, karena hakekatnya, perbuatan melukai, membunuh datang dari sifat-sifat alamiah kita yang tidak terkendali, termasuk dari kehendak dan niat. Sebagai sebuah ikhtisar, penulis ingin menyampaikan bahwa kekerasan dalam hidup ini tidak mungkin dihapuskan, mungkin hanya bisa dikurangi atau dikendalikan. Tentang kekerasan yang dihasilkan manusia sepanjang hayatnya, telah lama dipikirkan 158/ Ahimsa, dalam teropong Filsafat Antropologi Thomas Hobbes melalui Leviathan yang menyatakan bahwa manusia sudah secara alamiah, dari dalam dirinya sendiri, dipenuhi nafsu bahkan serakah untuk berkuasa. Kekuasaan itu bukan hanya dari manusia atas manusia lainnya, tapi juga hubungan manusia dengan sistem negara. Dus, dalam proses merengkuh kekuasaannya, sering manusia mengiris jalan centang perentang kekerasan. Sebagian besar konsep manusia dari sudut pandang empiris-materialistik Hobbes ini masih diamini. Dimensi kekerasan yang bersifat abadi itu, tidak bisa diselesaikan dengan cara yang justru bersifat temporal. Sebabnya, seperti pandangan kaum Aristotelian ataupun Skolastik yang menganggap aksiden tidak selalu adalah substansi, meski aksiden punya fungsi mendeterminasi substansi, sehingga merahnya mawar adalah mawar itu sendiri, padahal tidak sesederhana itu. Aksiden dan substansi boleh jadi memiliki ruang dan waktu yang berbeda. Keduanya juga adalah sebuah eksistensi. Sehingga determinasi aksidental terhadap substansi, misalnya, juga akan mengandung keterbatasan. Jadi, instanisme resolusi yang ditawarkan selama ini mungkin menyembuhkan kulit luar (aksiden), tetapi belum tentu isi atau apa yang terjadi di dalamnya (substansi). Berbagai pilihan resolusi yang ada sering dianggap sementara. Ahimsa hadir untuk menyambungkan dengan tepat antara “obat” dan “penyakit”, sehingga ada kesembuhan total antara jasamani dan rohani. Ahimsa adalah jalan pertobatan sepanjang hayat. Tidak mudah tentu saja, bahkan teramat sulit, tetapi Gandhi telah memperlihatkan keberhasilannya, bahkan dalam lingkup yang sangat besar: negara! Ia memulai dari dirinya sendiri, selanjutnya konsistensi menjadi medan ujian yang sesungguhnya. Ahimsa adalah “proyeksi keabadian” untuk menyelesaikan kekerasan, salah satu “masalah keabadian” [*] 159/ Ahimsa, dalam teropong Filsafat Antropologi EPILOG: Ahimsa, dari Gerakan Massa ke Individual ..................................................................................................................................................................... Gagasan dan pemikiran Gandhi, utamanya tentang gerakan moral Ahimsa sesungguhnya tidak sebesar apa yang telah nyata diperjuangkan Gandhi. Sesungguhnya pula gagasan itu belum pernah selesai dan berhenti, sebab substansi gagasan itu selalu lebih panjang dari usia pencetusnya sendiri. Gagasan Gandhi akan terus hidup setelah kematiannya. Dan sebenarnya, apa yang telah digagasnya hanyalah penggalan dari cita-cita besarnya bagi kemanusiaan. Gerakan moral Ahimsa mungkin dapat disebut pemikiran revolusioner, hanya saja Gandhi memodifikasinya menjadi gerakan yang lebih humanis, dan dengan cara-cara baru yang didasarkan atas nilai-nilai kemanusiaan dan tanpa kekerasan. Itulah mengapa, Gandhi tidak terlalu menyukai revolusi ala Marx, Lenin dan tokoh-tokoh revolusi lainnya yang harus mengorbankan satu atau dua generasi demi kesejahteraan massa, atau mengorbankan kelas-kelas sosial demi kebahagiaan kelas tertentu. Gandhi banyak mengambil pelajaran dari keberhasilan eksperimen pertamanya di Afrika Selatan dan sukses di India yang memperoleh kemerdekaan tanpa harus meneteskan banyak darah. Sebagaimana juga tokoh-tokoh masa lalu, macam Marx cs, yang belakangan banyak menuai kritik terlalu utopia untuk ukuran jaman hari ini, Gandhi pun tak bisa menghindar dari bayangan utopia, apalagi Ahimsa akan selalu berhasil ditiap kontesk jaman. Namun, pengandaian ini sangat mungkin terlalu distorsif karena adanya ruang-waktu-tempat yang berbeda dengan kondisi sekarang. Kesalahan lainnya adalah saat ini kekerasan tidak melulu tampil dengan wajah yang kasat di mata, seperti perang, teror dan kekerasan fisik lainnya. Sudah sejak jaman Sang Buddha hingga Sokrates telah terjadi kekerasan dengan cara yang halus. Menurut hemat penulis, Gandhi mengandaikan bahwa Ahimsa akan berhasil dalam segala bidang, namun dengan rujukan total seperti yang telah dilakukannya. 161/ Ahimsa, dalam teropong Filsafat Antropologi Pada jaman atau konteks perjuangan Gandhi di masa lampau, Ahimsa mungkin dapat dilakukan dengan mudah. Keberhasilan ini boleh jadi disebabkan konteks waktu perjuangan Gandhi yang tepat maupun kesederhanaan pola berpikir banyak orang. Kaum realis politik sering mengatakan bahwa cita-cita dan pemikiranpemikiran Gandhi terbukti naïf dalam riil politik India dewasa ini. Penggambaran Gandhi yang begitu agung yang memenuhi kekaguman rakyat India yang disimbolisasikan melalui lukisan dan patung perunggu disetiap perempatan jalan umum, rakyat India sendiri boleh dikatakan melupakan pesan-pesan substansial Sang Mahatma. Contoh paling nyata tentang hal ini adalah bagaimana egoisme politik antara India modern dengan Pakistan, juga sebagian besar bangsa-bangsa Asia lainnya, hingga hari ini tetap berlangsung sengit. Perang diperbatasan Kashmir masih terus tersulut. Begitu juga “pertarungan” dan unjuk kekuatan melalui pamer bom dan nuklir, sering menjadi isu internasional yang sensitif; sesuatu yang dulu oleh Gandhi sangat ditentang dan diprotes dengan keras. Kritik sinis ini menjadi penting untuk sekadar mengingat bahwa riil politik pada jaman Gandhi tidaklah kurang lebih kerasnya dibandingkan dengan jaman kita dewasa ini. Bagi penulis, Gandhi juga kedengaran sama idealistiknya pada jamannya. Kesulitan yang akan teramat sulit untuk dirasakan ketika kekerasan tersebut menyudutkan kita pada posisi tanpa berani mengambil keputusan. Mungkin tidak disebut ambigu, paradoks, ambivalen atau entah apa namanya, tetapi ada kalanya kita dapat saja diberdaya karena tiadanya pilihan yang tepat dengan hasil yang dianggap benar menurut situasinya. Sebagai contoh, bagaimana kita mampu menegakkan kesadaran kita dengan “hanya” setia pada aturan Ahimsa yang ketat, ketika kita, misalnya sebagai seorang ayah dari anak perawan kita diperkosa tepat di depan mata. Apa yang harus dilakukan? Jika jawaban atas pertanyaan ini dibawa ke wilayah teologi, di mana Hindu membenarkan pembunuhan menurut dharma yang berlaku pada saat itu, maka diskusi ini (mungkin) akan segera berakhir. 162/ Ahimsa, dalam teropong Filsafat Antropologi Sementara untuk ukuran jaman hari ini, di mana bentukbentuk kekerasan yang begitu kompleks, baik yang mengambil bentuk fisik maupun non-fisik, Ahimsa mungkin akan terlihat sedikit utopia. Ini disebabkan kesulitan yang juga teramat besar untuk menghadapi kekerasan-kekerasan itu, meski banyak pola yang diperkenalkan, serta tidak sesederhana yang diandaikan para Ahimsais. Gandhi sendiri harus membutuhkan lebih 40 tahun untuk membuktikan keberhasilan gerakan moralnya ini. Dalam kesulitan seperti ini, Ahimsa dapat menjadi sikap dasar yang fundamental dalam menghadapi kekerasan. Jika hal ini secara konsisten dilakukan, terlebih untuk diri sendiri saja, tentu Ahimsa bukan utopia, bukan mimpi lagi. Namun, untuk dapat dijadikan sikap dasar bagi semua orang, terlebih dengan jumlah yang besar, mungkin akan sangat sulit. Sejarah keberhasilan dan kegagalan gerakan moral Ahimsa sudah membuktikan bahwa dibutuhkan totalitas dan konsistensi dalam menjalaninya. Dalam banyak kritik terhadap Ahimsa, ajaran ini masih menyisakan peluang besar, terutama, sekali lagi untuk diri sendiri. Syarat utamanya, menemukenali diri sendiri, sebagaimana Sokrates mendengar satu perintah di bawah langit Delphi: “Kenalilah dirimu sendiri!” Svaha [*] 163/ Ahimsa, dalam teropong Filsafat Antropologi DAFTAR PUSTAKA Adian, Donny Gahral. Matinya Metafisika Barat. Jakarta: Komunitas Bambu, 2001. Amaladoss, Michael. Teologi Pembebasan Asia. terjm. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2001. Ambler, Rex. Gandhian Peacemaking, dalam Paul Smoker, Ruth Davies dan Barbara Munske, A Reader in Peace Studies. Oxford: Pergamon Press, 1990. Ananthanarayanan, N. From Man to God-Man. New Delhi: N. Ananthanarayan, 1970. Arendt, Hannah. Teori Kekerasan. terjm. Yogyakarta: LPIP, 2003. Aristoteles. De Anima terjm. Hugh Lawson-Tancred. London: Penguin Books, 1986. Aziz, M., Imam, M., Jadul Maula dan Ellyasa KH. Dharwis. penyunting, Agama, Demokrasi dan Keadilan. Jakarta: Gramedia, 1993. Bagus, Lorens. Metafisika. Jakarta: Gramedia, 1991. __________. Kamus Filsafat. Jakarta: Gramedia, 1996. Bakker, Anton. Ontologi Metafisika Umum. Yogyakarta: Kanisius, 1992. __________. Antropologi Metafisik. Yogyakarta: Kanisius, 2000. Bakker, J.W.M. Filsafat Kebudayaan. Yogyakarta: Kanisius, 1994. Bertens, K. Etika. Jakarta: Gramedia, 2001. _________. Filsafat Barat Abad XX, Jilid II. Jakarta: Gramedia, 1996. Bose, Anima. Dimensions of Peace and Nonviolence, The Gandhian Perspective. Delhi: Gian Publishing House, 1987. 167/ Ahimsa, dalam teropong Filsafat Antropologi Boulding, Kenneth E. Peace Theory dalam Paul Smoker, Ruth Davies dan Barbara Munske (Eds), A Reader In Peace Studies. Oxford: Pergamon Press, 1990. Bruner, Edward. Experience and Its Expressions dalam Bruner (ed) The Anthropology of Experience. Chicago: University of Illinois, 1986. Cassirer, Ernst. Manusia dan Kebudayaan: sebuah esei tentang manusia. terjm. Jakarta: Gramedia, 1990. Devaraja, N.K. Philosophy, Religion and Culture. New Delhi: Motilal Banarsidas, 1974. Dikshit, Sudhakar S. I am All: a Cosmic Vision of Man. Bombay: Chhaya Arya for Chetana Pvt. Ltd., 1988. Drijarkara. Filsafat Manusia. Yogyakarta: Kanisius, 1969. Fischer, Louis. Mahatma Gandhi, Penghidupannja dan Pesannja untuk Dunia. terjm. Djakarta: PT Pembangunan, 1967. Galtung, Johan. Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization. Oslo: PRIO, 1996. Geertz, Clifford. The Interpretation of Cultures: Selected Essays. London, Hutchinson & CO Publisher LTD, 1973. (The Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture [1973a] Hadiwijono, Harun. Sari Sejarah Filsafat Barat 2. Yogyakarta: Kanisius, 2001. Hegel, GWF. “Phenomenology of Spirit” pada Walter Kaufmann and Forrest E. Baird, From Plato to Nietszche. NJ: Prentice Hall, 1994. Heraty, Toety. Aku dalam Budaya. Jakarta: Pustaka Jaya, 1984. Hidayat, Komarudin dan Muhammad Wahyuni Nafis. Agama Masa Depan: Perspektif Filsafat Perennial. Jakarta: Paramadina, 1995. Iyer, Raghavan. The Moral and Political Thought of Mahatma Gandhi. New Delhi: Oxford University Press, 1973. 168/ Ahimsa, dalam teropong Filsafat Antropologi Kaufmann, Walter and Forrest E. Baird. From Plato to Nietzsche. NJ: Prentice Hall, 1994. Knitter, Paul F. One Earth Many Religions: Multifaith Dialogue & Global Responsibility. terjm. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003. Kripalani, Krishna. All Men are Brothers: Life and Thought of Mahatma Gandhi as Told in His Own Words. India: Jitendra T. Desai, 1960. Kripalani, J.B. Gandhi: His Life and Thought. New delhi: Publications Division, 1970. Kumarappa, Bharatan. (ed.) Satyagraha. (Non-violence Resistance) India: Jivanji Dahyabhai Desai, 1951. Lanur, Alex. Diktat dan Bahan Kuliah Filsafat Manusia. Universitas Indonesia. Leahy, Louis. Siapakah Manusia? sintesa filosofis tentang manusia. Yogyakarta: Kanisius, 2001. Leenhouwers, P. Manusia dalam Lingkungannya. terjm. Jakarta: Gramedia, 1988. Madrasuta, Ngakan dan Sang Ayu Putu Renny. 10 Tokoh Pembaru dan Pemikir Hindu. terjm. Denpasar: Manikgeni, 2002. _________________. Gandhi dalam Dialog Hindu-Kristen. terjm. Surabaya: Paramita, 2002. Magnis-Suseno, Franz. 13 Tokoh Etika. Yogyakarta: Kanisius, 1997. __________________. Model Pendekatan Etika. Yogyakarta: Kanisius, 1997. __________________. Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral. Yogyakarta: Kanisius, 1993. Maharaj, Sri Nisargadatta. I am That. New Delhi: Chetana, 1992. Malinowski, B. Argonauts of the Western Pacific. Waveland Press Inc., 1984 (1922). 169/ Ahimsa, dalam teropong Filsafat Antropologi M. Borchet, Donald. (ed.) The Encyclopedia of Philosophy (Supplement) Simon & Schuster. New York, 1996. Mehta, Rohit. The Calls of The Upanisads. New Delhi: Motilal Banarsidas, 1990. Mehta, Mohan Lal. Jaina Philosophy. New Delhi: P.V. Research Institute, 1971. Mehta, Ved. Ajaran-ajaran Mahatma Gandhi. terjm. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002. Ming, Chau. Mengenal Beberapa Aspek Filsafat Konfusiusisme, Taoisme dan Buddhisme. Jakarta: Akademisi Buddhis Nalanda, 1985. Nakamura, Hajime. A Comparative History of Ideas. New Delhi: Motilal Banarsidas, 1992. Nanda, B.R. Gandhi and His Critics. Delhi: Oxford University Press, 1985. Nasr, Seyyed Hossein. Religion and the Order of Nature. New York: Oxford University Press, 1996. Nicholson, Michael. Mereka yang berjasa bagi dunia: Mahatma Gandhi. terjm. Jakarta: Gramedia, 1994. Nugroho, Alois A. Pemikiran Etika yang “Jatuh Bangun,” dalam Indonesia Abad XXI, Jakarta: Kompas, 2000. Oka, Gedong Bagus. Gandhi sebuah Otobiografi. terjm. Denpasar: Yayasan Bali Canti Sena, 1978. _________________. Gandhi sebuah Otobiografi. terjm. Jakarta: Sinar Harapan, 1982. Parekh. Bhikhu. Gandhi’s Political Philosophy: A Critical Examination. London: The MacMillan Press, 1989. Permata, Ahmad Norma. (ed.) Perennialisme: Melacak Jejak Filsafat Abadi. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996. Plato. terjm. Francis McDonald Comford, The Republic of Plato. Oxford: Oxford University Press, 1970. Poespowardojo, Soerjanto dan K. Bertens. Sekitar Manusia. Jakarta: Gramedia, 1985. 170/ Ahimsa, dalam teropong Filsafat Antropologi Polanyi, Michael. Kajian tentang Manusia. terjm. Yogyakarta: Kanisius, 2001. Putra, Ngakan Putu (ed). Upanisad Himalaya Jiwa, Intisari Upanisad, terjemahan dari The Upanisads oleh Juan Mascaro dan A Concise Encyclopedia of Hinduism oleh Swami Harshananda. Penerjemah Sang Ayu Putu Reny. Jakarta: Media Hindu, 2010. Radhakrishnan, S. and P.T. Raju. The Concept of Man: a Study in Comparative Philosophy. Delhi: Motilal Banarsidass 1992. Rama, Swami. Perennial Psychology of the Bhagavad-Gita. USA: The Himalayan International Institute of Yoga Science and Philosophy of the USA, 1998. Raphael. Tat Tvam Asi, that thou art. New Delhi: Motilal Banarsidass, 1992. Santoso, Thomas. Teori-Teori Kekerasan. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002. Schuon, Frithjof. Mencari Titik Temu Agama-Agama. terjm. Jakarta: Obor, 1987. Smith, Dan. “Legitimacy, Justice and Preventive Intervention” dalam Peter Wallenstein (ed.), Preventing Violent Conflict: Past Record and Future Challenge. Stockhlm: Elanders Gotab, 1998. Sing, Maharaj Sardar Bahadur Jagat. The Science of The Soul. Punjab: Radha Soami Satsang BEAS, 1959. Snijders, Albert. Antropologi Filsafat. Manusia Paradoks dan Seruan. Yogyakarta: Kanisius, 2004. Siswanto, Joko. Sistem-Sistem Metafisika Barat: dari Aristoteles sampai Derrida. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998. Soemargono, Soejono. (alih bahasa), Berpikir Secara Kefilsafatan. Yogyakarta: Nur Cahaya. Spradley, James P. Metode Etnografi. Terjm. Misbah Zulfa Elizabeth dari The Ethnographic Interview, 1979. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007. 171/ Ahimsa, dalam teropong Filsafat Antropologi Starke, J.G. Q.C. An Introduction to the Science of Peace (Irenology). Leiden: A.W. Sitjhoff’s Uitgeversmaatscappij N.V., 1968. To, Tin Anh. Nilai Budaya Timur dan Barat: Konflik atau Harmoni? Jakarta: Gramedia, 1985. Van Schie, G. Manusia Segala Abad Pencari serta Pencipta Hidupnya. Jakarta: Obor, 1996. Wardhana, Made. Vegetarian dari A-Z. Denpasar: VIP, 2016. Wasito, Hermawan. Pengantar Metodologi Penelitian. Jakarta: Gramedia, 1995. Wolpert, Stanley. Mahatma Gandhi, sang penakluk kekerasan, hidupnya dan ajarannya. terjm. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001. Zaehner, Robert C. Kebijaksanaan dari Timur, beberapa aspek pemikiran Hinduisme. terjm. Jakarta: Gramedia, 1993. Zimmer, Heinrich. Sejarah Filsafat India. terjm. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003. Artikel Cetak dan Virtual: Hinduism Today April/May/June, 2003 Influence Champions of Nonviolence. Majalah Filsafat Driyarkara Thn. XV, No. 1 1988 dan Thn XXI, No. 4 1994/1995. www.mkgandhi.org diakses tanggal 10 Oktober 2003 www.transcend.org diakses tanggal 10 Oktober 2003 www.gandhiinstitute.org diakses tanggal 11 Oktober 2003 http://indonesian.irib.ir/editorial/fokus/item/ 60291mencermati_Aksi_Bakar_Diri_Terbaru_di_Tunisia diakses tanggal 28 Desember 2016. http://www.berdikarionline.com/10-presiden-korbanpembunuhan-politik/diakses tanggal 5 Januari 2017 https://id.wikipedia.org/wiki/Kematian_John_Lennon diakses tanggal 5 Januari 2017 172/ Ahimsa, dalam teropong Filsafat Antropologi