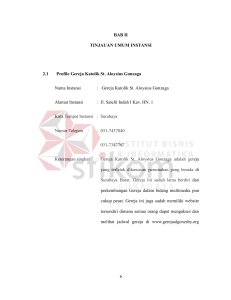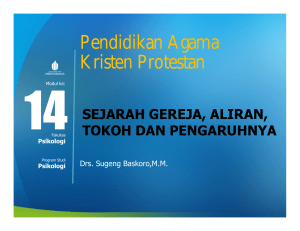menuju teologi rekonsiliasi
advertisement

MENUJU TEOLOGI REKONSILIASI MENCARI DASAR REKONSILIASI BAGI GEREJA PASCAKONFLIK MELALUI PROSES MENGINGAT DAN MENGAMPUNI1 BINSAR JONATHAN PAKPAHAN2 ABSTRAK Rekonsiliasi diperlukan di antara gereja-gereja yang berpisah akibat konflik sebagai sebuah usaha untuk mencapai pendamaian dan gereja yang esa. Usaha ini dimulai dengan mencari ekklesiologi yang benar dari makna teologis Perjamuan Kudus sebagai lex orandi teologi gereja yang baik. Selain tempat rekonsiliasi, Perjamuan Kudus adalah sebuah tempat di mana hospitalitas terhadap seluruh makhluk dilaksanakan. Karena itu gereja-gereja diajak untuk kembali memikirkan dan memperbarui teologi Perjamuan Kudus mereka, untuk mencapai rekonsiliasi dengan Allah, umat dan seluruh ciptaan. KATA-KATA KUNCI Pertumbuhan, perpecahan, konflik, rekonsiliasi, lex orandi, Perjamuan Kudus, pengampunan, liturgi, ekklesiologi, hospitalitas PENDAHULUAN Pertumbuhan kekristenan di Asia selama satu abad terakhir didukung oleh beberapa hal seperti kondisi regional, pertumbuhan ekonomi, kebebasan berekspresi yang semakin luas, dan terbukanya jalur transportasi dan komunikasi ke daerah-daerah yang selama ini dianggap terpencil. Sejalan dengan kondisi yang semakin terbuka ini, kaum Pentakostal, secara khusus, 1 Makalah Kuliah Umum STT HKBP Pematangsiantar, 11 Agustus 2016. Beberapa materi dari makalah ini sudah diterbitkan di Jurnal Diskursus Vol. 12 No. 1, Oktober 2013. pp. 253-277; Jurnal Gema Teologi Vol. 37 No. 1, April 2013. pp. 47-60; dan Indonesian Journal of Theology Vol. 2 No. 1, 2014. pp. 42-64. 2 Pendeta HKBP yang diutus sebagai dosen Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, menjabat sebagai Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan, pengampu matakuliah Filsafat, Etika, dan Teologi Publik. Memperoleh gelar Doctor of Philosophy (Ph.D.) dari Fakultas Teologi Vrije Universiteit, Amsterdam (2011) dalam bidang Teologi Sistematika. Anggota Komisi Teologi HKBP serta Badan Penelitian dan Pengembangan HKBP. Publikasi utamanya adalah God Remembers: Towards a Theology of Remembrance as a Basis of Reconciliation in Communal Conflict (Amsterdam: VU University Press, 2012). Telah menerbitkan berbagai artikel di jurnal internasional dan Indonesia. Sekarang sedang menyelesaikan disertasi habilitasi di Evangelisch-Theologische Fakultät, Westfälische WilhelmsUniversität (WWU) Münster, Jerman (sejak 2016), atas tema peran rasa malu dan hormat di komunitas Kristen Indonesia dalam praktik pengampunan dan kontribusinya terhadap pembentukan norma masyarakat Indonesia. 1 2 mengalami pertumbuhan yang pesat dalam 30 tahun terakhir. Perkembangan ini juga terjadi di Pentakostal dan kharismatik. Namun demikian, pertumbuhan ini bisa kita lihat secara positif, yaitu bahwa gereja memang bertumbuh; dan secara negatif yaitu bahwa berkembangnya jumlah disintegrasi dan konflik antara kelompok-kelompok Kristen. Dalam sebuah percakapan dengan Prof. Jan S. Aritonang mengenai konflik gereja, beliau Menilik sejarah, konflik bukanlah sebuah fenomena luar biasa dalam gereja. Aritonang mengatakan bahwa sejak Reformasi, Gereja selalu mengalami konflik dalam berbagai bentuk sehingga menghasilkan gereja-gereja baru (Aritonang, 1995). Konflik tidak harus selalu dipandang negatif. Jika konflik dikelola dengan baik, maka dia dapat menghasilkan pertumbuhan yang positif. Konsultasi Teologi Nasional yang diselenggarakan oleh Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia pada 31 Oktober 4 November 2011, menyadari trend ini. Dengan tema Berteologi dalam Konteks: Meretas Jalan Menuju Perdamaian, Keadilan, dan Keutuhan Ciptaan (Aritonang, 2012), Konsultasi ini menunjukkan bahwa gereja-gereja di Indonesia memiliki kesadaran untuk menjadi agen pendamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Pertanyaan penting yang dapat kita ajukan adalah, bagaimana gereja bisa memiliki atau membangun teologi yang membawa pendamaian bagi dirinya sendiri, terutama bagi gereja-gereja yang lahir akibat konflik? PERTUMBUHAN DAN PERPECAHAN GEREJA Gereja-gereja di Indonesia menyadari pentingnya menjaga semangat ucapan Yesus, (ut omnes unum sint) (Yoh. 17:20-26). Akibat kerinduan akan kesatuan gereja-gereja di Indonesia, dan juga kepentingan komunikasi dan koordinasi, sinodesinode gereja di Indonesia memandang perlu adanya sebuah lembaga koordinasi di aras nasional. Dewan Gereja-gereja di Indonesia yang lahir pada tahun 1950 adalah hasil dari semangat persatuan ini. Namun demikian, dalam perkembangan berikutnya, alih-alih memiliki satu lembaga persekutuan gereja-gereja tingkat nasional, Indonesia sekarang memiliki 7 lembaga persekutuan gereja tingkat nasional yaitu Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Persekutuan Gereja-gereja Pentakosta Indonesia (PGPI) dan Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia (PGLII), Gereja Bala Keselamatan, gabungan Gereja-gereja Baptis Indonesia, Gereja Masehi Advent Hari Ke-7 (MAH) dan PGTI (persekutuan Gerejagereja Tionghoa Indonesia). Empat persekutuan terakhir sebenarnya hanya mewakili denominasi masing-masing, namun mereka menyatakan dirinya ada dalam tingkat nasional. Perkembangan jumlah gereja juga diikuti oleh perkembangan jumlah persekutuan gereja aras nasional. Dari tujuh persekutuan gereja-gereja aras nasional, tiga di antaranya terdiri dari berbagai sinode gereja. Persekutuan Gereja-gereja Indonesia yang memiliki anggota berlatar belakang mainstream memiliki 89 anggota (Website PGI 2014), PGLII yang mengkhususkan diri 3 untuk gereja dan lembaga Injili memiliki 92 sinode gereja sebagai anggotanya (83 anggota aktif) (Website PGLII 2013), dan PGPI sebagai lembaga persekutuan gereja Pentakostal memiliki 81 anggota (Website PGPI 2013). Ada tiga sinode gereja yang menjadi anggota dari semua persekutuan ini, yaitu Gereja Bethel Indonesia (GBI), Gereja Gerakan Pentakosta (GGP), dan Gereja Tuhan di Indonesia.3 Sinode-sinode gereja yang baru muncul dari pemisahan diri dari sinode induknya atau pendewasaan pos jemaat menjadi jemaat penuh. Pendirian sebuah sinode gereja baru lebih banyak lahir dari perbedaan nondoktrinal dibandingkan isu penting seperti baptisan, trinitas, perjamuan kudus, atau ekklesiologi gereja. Contoh peningkatan jumlah sinode gereja yang terjadi pada gereja-gereja arus utama bisa dilihat dalam pertumbuhan gereja-gereja di Sumatera Utara.4 Pertumbuhan jumlah gereja di Sumatera Utara datang dari beberapa faktor-faktor dan dua faktor utamanya adalah bahasa dan budaya. Sinode gereja seperti GKPA (Gereja Kristen Protestan Angkola), GKPPD (Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi), dan GKPS (Gereja Kristen Protestan Simalungun) adalah gereja yang mandiri karena perbedaan budaya dan bahasa dengan Huria Kristen Batak Protestan yang 5 Alasan perpisahan juga sering dipengaruhi oleh faktor kekuasaan finansial (Simanjuntak, 2009). Ingatan proses perpisahan pun tidak sama di antara gereja induk dan gereja baru, ada yang melihatnya sebagai pendewasaan dan sebagai pertengkaran (Dasuha dan Sinaga, 2003).6 Pertumbuhan dan perpisahan gereja dalam tingkat sinodal ini bisa dilihat sebagai berkat dan masalah. Jika perkembangan terjadi melalui perpisahan dan konflik, apakah gereja-gereja ini sudah berdamai? Jika belum, bagaimana gereja-gereja bisa mempertanggungjawabkan panggilannya sebagai pembawa damai, sementara pendamaian di antara gereja-gereja yang memisahkan diri dan berkonflik belum pernah terjadi? Apakah sikap diam dan melanjutkan pekerjaan dan pelayanan masing-masing menjadi pilihan yang baik? 3 Keanggotaan ganda sepertinya tidak dilarang dalam keanggotaan lembaga gereja aras nasional ini. Enam anggota PGI juga adalah anggota PGPI, 1 anggota PGI juga adalah anggota PGLII, dan 15 anggota PGLII adalah anggota PGPI. 4 Sebagai catatan, DGI (kemudian berubah menjadi PGI) didirikan dan didukung oleh 50 sinode gereja pada tahun 1950, dan pada tahun 2013, PGI memiliki 88 anggota. Banyak anggota baru dari PGI ini datang dari perpecahan dengan gereja induknya. 5 Gereja-gereja ini berasal dari suku Batak yang memiliki enam sub-suku yang memiliki bahasa dan dialek yang berbeda: Karo, Pakpak atau Dairi, Simalungun, Toba, Angkola, dan Mandailing. Lihat Andar M. Lumbantobing, Makna Wibawa Jabatan Dalam Gereja Batak (Jakarta: BPK GM, 1996), 1; dan Lothar Schreiner, Adat dan Injil: Perjumpaan Adat dengan Iman Kristen di Tanah Batak (Jakarta: BPK GM, 2000). Umumnya, pada saat ini HKBP hanya mengakomodir bahasa Batak Toba dan Indonesia. 6 Salah satu contoh dari perpecahan ini adalah pendewasaan GKPS dari HKBP. HKBP dan GKPS sepertinya memiliki dua versi cerita perpisahan. HKBP menulis bahwa proses ini berlangsung dengan damai, sementara itu sebuah buku karya pendeta GKPS Juandaha Raya P. Dasuha dan Martin Lukito Sinaga bercerita tentang versi lain dari perpisahan ini. 4 Fokus makalah ini adalah untuk mencari landasan teologis untuk rekonsiliasi bagi gerejagereja yang lahir dari konflik dalam proses mengingat dan memaafkan. Setelah melalui proses tersebut, kita juga akan melihat makna teologis dari Perjamuan Kudus sebagai lex orandi dari gereja yang membuka kemungkinan untuk terjadinya rekonsiliasi. PENGAMPUNAN DAN REKONSILIASI Rekonsiliasi adalah pemulihan hubungan yang rusak antara Allah dan manusia melalui pengorbanan Kristus untuk pengampunan dosa. Gereja (komunitas manusia percaya) menjadi suci karena adanya rekonsiliasi antara dirinya dan Allah. Gereja adalah tempat di mana rekonsiliasi dinyatakan karena dia adalah pusat dari karya keselamatan Allah. Melalui dan darinya, orang yang telah didamaikan dengan Allah akan dimampukan oleh Roh Kudus untuk berdamai dengan yang lain. Rekonsiliasi adalah hadiah Allah untuk ciptaan-Nya. Hadiah Allah ini juga menuntut kita untuk melakukan rekonsiliasi dengan makhluk ciptaan lainnya. Berada dalam pendamaian dengan yang lain berarti dibebaskan dari hubungan yang tidak damai sesama manusia. Dalam teologi Kristen, rekonsiliasi selalu dihubungkan dengan tindak pengampunan. Tindak pengampunan menjadi langkah awal menuju sebuah rekonsiliasi sejati (Jones, 2000: 122). Rodney L. Petersen, teolog Amerika bidang etika dan konflik, mencatat tiga elemen penting dalam ajaran Yesus mengenai pengampunan, yaitu bahwa (1) dia adalah hadiah dari Allah; (2) Yesus memberikan dirinya untuk pengampunan dosa; dan (3) pertobatan berhubungan dengan memaafkan (2001: 14). Allah adalah aktor utama dalam relasi memaafkan antara Allah dan manusia, antarmanusia, dan seluruh ciptaan (lihat Clark, 2003: 78). Tanggung jawab manusia adalah untuk meniru tindakan Allah ini dan mengusahakan rekonsiliasi dengan manusia lain. Hubungan antara pengampunan dan rekonsiliasi dalam teologi Kristen mendapat tantangan dalam penelitian mengenai pengampunan dalam ilmu sosial. Penelitian terbaru dalam bidang psikologi mempertanyakan apakah tindak memaafkan betul-betul diperlukan untuk rekonsiliasi. Menurut mereka, rekonsiliasi dapat dicapai tanpa melalui tindakan memaafkan dan demikian juga sebaliknya (de Waal dan Pokorny, 2005: 17-32). Rekonsiliasi adalah jalan penyelesaian konflik yang terbaik. Rekonsiliasi berasal dari kata Latin, reconciliare, dari akar kata conciliare menjadi: memulihkan hubungan persahabatan, membuat sesuatu menjadi kompatibel, menerima perbedaan. Ide utama dari kata rekonsiliasi adalah membawa kembali bersama atau menyatukan kembali apa yang sudah terpisah dalam konflik. Dengan rekonsiliasi, pihak-pihak yang berpisah karena perbedaan kembali disatukan. Ada berbagai macam cara untuk mencapai rekonsiliasi. Cara paling baik adalah melalui pengampunan. Dalam teologi, pengampunan adalah langkah penting dalam mencapai rekonsiliasi. Tujuan dari pengampunan dalam teologi Kristen adalah rekonsiliasi. Karena 5 pengampunan yang dimediasi oleh Kristus, hubungan Allah dan manusia menjadi disatukan mencapai rekonsiliasi dan melibatkan panggilan untuk menyambut kasih Allah yang penuh pengampunan dengan menciptakan komunitas orangPengampunan adalah tindakan yang mendahului rekonsiliasi, menyingkirkan semua halangan rekonsiliasi dan bertujuan untuk mencapai komunitas yang harmonis kembali. Teologi Kristen mengenai pengampunan dan rekonsiliasi menerima tantangan dari penelitian di bidang ilmu sosial. Penelitian bidang psikologi mempertanyakan apakah rekonsiliasi membutuhkan pengampunan. Menurut mereka, rekonsiliasi bisa dicapai tanpa pengampunan, begitu juga sebaliknya pengampunan bisa tercapai tanpa rekonsiliasi. Dalam Yudaisme, pengampunan juga dapat terjadi tanpa harus ada rekonsiliasi, dan demikian juga sebaliknya. Seseorang bisa memaafkan pelaku kejahatan terhadapnya dan memutuskan untuk tidak memiliki hubungan apapun dengan pelaku tersebut. Seseorang juga dapat memutuskan untuk kembali dalam hubungan sebelumnya dengan pelaku kejahatan tersebut tanpa memaafkannya. Dalam proses pengampunan, sang pelaku kejahatan harus melewati proses tesuvah (return/pertobatan), yang meliputi sejumlah langkah: pengakuan kejahatan sebagai dosa, penyesalan, menolak melakukan dosa itu lagi, dan membayar restitusi terhadap korban, serta pengakuan. Jika sang pelaku gagal melakukan langkah-langkah ini, maka sang korban memiliki hak untuk tidak mengampuninya. Ketika langkah-langkah tersebut ditempuh, rekonsiliasi tetap merupakan pilihan dan bukan keharusan. Sementara itu, ada beberapa penelitian di bidang filosofi yang mendukung paham rekonsiliasi membutuhkan pengampunan. Trudy Govier, seorang filosof, mengatakan bahwa orang yang memiliki konflik di masa lalu memang bisa kembali bersama tanpa membicarakan masa lalunya (Govier, 2002: 141). Namun Govier berpendapat bahwa rekonsiliasi jenis ini tidak akan bertahan lama. Istilah rekonsiliasi dalam jenis ini telah diminimalisir artinya menjadi nonviolent co-existence kepercayaan di antara pihak yang berkonflik. Kepercayaan bisa diperoleh melalui perubahan sikap (baca: pembaruan), dan perubahan sikap datang dari pengampunan. Govier berkata, kerjasama dan daya tahan (coDengan demikian, pengampunan adalah faktor yang melekat pada rekonsiliasi. Namun, ada juga beberapa proses rekonsiliasi yang mencoba melepaskan diri dari pengampunan. Mari kita coba mengaplikasikan penelitian ini atas konflik dalam gereja. Apabila ada kelompok yang bertikai dalam gereja, maka tindak memaafkan tanpa rekonsiliasi akan berujung kepada pemisahan kedua gereja yang bertikai. Dalam langkah ini, kedua kelompok memutuskan untuk saling memaafkan namun tidak mau bekerjasama dalam satu gereja lagi. Sementara itu, jika kelompok yang bertikai memilih rekonsiliasi tanpa adanya pengampunan, maka mereka akan tetap berada dalam satu gereja tanpa pernah betul-betul menyelesaikan luka masa lalunya. 6 Pendekatan dengan cara ini akan membuka konflik itu muncul kembali sewaktu-waktu, baik dalam bentuk yang sama maupun berbeda. Kedua kemungkinan di atas tidak menunjukkan prospek yang baik untuk tugas gereja menjalankan pendamaian dan pengampunan. Ketika kelompok bertikai memutuskan untuk berpisah, pertanyaan yang harus diajukan kepada mereka adalah apakah pengampunan sudah terjadi. Jika pengampunan sudah terjadi, mengapa mereka masih tetap berpisah? Jika kelompok yang berpisah memutuskan untuk tetap bersatu tanpa adanya pengampunan, maka rekonsiliasi yang terjadi bukanlah rekonsiliasi sejati karena konflik dapat pecah kembali sewaktu-waktu. Situasi ideal untuk gereja-gereja yang mengalami konflik adalah untuk berdamai dan saling memaafkan. Namun, hal ini tidak mudah untuk dicapai. Ketika konflik terjadi dalam gereja, kata pengampunan muncul dengan seketika. Karena kita adalah manusia yang menerima pengampunan, maka kita juga diminta untuk mengampuni yang lain. Namun demikian, pengampunan yang seharusnya menjadi sifat alami gereja ternyata tidak mudah untuk dilakukan oleh gereja yang berkonflik. Rekonsiliasi sejati memerlukan pengampunan, dan pengampunan memerlukan waktu. Pengampunan bukanlah hal murahan. Bonhoeffer menjelaskan bahwa cheap grace adalah mengkhotbahkan pengampunan yang tak membutuhkan pertobatan, baptisan tanpa disiplin gereja, dan perjamuan kudus tanpa pengakuan dosa, pengampunan dosa tanpa pengakuan (1966: 31). Kesadaran bahwa dirinya telah melakukan kesalahan diperlukan dalam pengampunan. Proses ini mengandaikan bahwa kita telah mengingat kesalahan yang terjadi di masa lalu dan mengakuinya sebagai sesuatu yang perlu diampuni. Martha E. Stortz merangkum langkahBertobat, mengingat, dan melakukan rekonsiliasi adalah tiga langkah yang memberi hidup dalam pengampunan. Mereka membawa kita menjauh dari kebalikannya yang mematikan: balas dendam, pelupaan, dan saling menuduh (2007: 14). Dengan demikian, langkah pertama dalam proses rekonsiliasi adalah mengingat apa yang terjadi dan bagaimana kita bisa menyelesaikannya (Stortz, 2007: 14; lihat Enright dan Fitzgibbons, 2000: 67-69). Pengampunan memiliki sifat komunal yang harus dilakukan dalam komunitas orang percaya (Jones, 1995: 163). Komunitas orang percaya adalah komunitas orang-orang yang diampuni yang dimampukan untuk mengampuni. Pengampunan yang dilakukan dalam komunitas menolak tujuan pengampunan terapis psikologi modern yang bersifat individual. Ketika gereja menghadapi konflik, dia menjadi agen dan objek dari rekonsiliasi. MENGINGAT DAN REKONSILIASI Belakangan ini, semakin banyak penelitian di bidang psikologi, sosiologi, dan filosofi yang menyatakan bahwa mengingat adalah cara yang lebih baik untuk menghadapi masa lalu yang menyakitkan daripada melupakan. Beberapa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di 7 berbagai negara telah ditetapkan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, mendengar suara korban, dan mencoba belajar agar peristiwa yang sama tidak terjadi di masa yang akan datang. Afrika Selatan telah mendirikan Truth and Reconciliation Commission untuk mengetahui cerita kekerasan yang terjadi di masa pemerintahan apartheid. Tujuan pendirian komisi ini adalah untuk membantu rakyat Afrika Selatan berdamai dengan masa lalunya dan maju menuju masa depan sebagai sebuah bangsa. Australia telah menetapkan 26 Mei sebagai Hari Maaf Nasional terhadap orang Aborigin, sebagai usaha untuk mendekatkan mereka dengan penduduk asli benua tersebut. Penelitian besar juga telah dilakukan setelah pembantaian orang Yahudi di masa Hitler sebagai usaha pembelajaran agar kejadian yang sama tidak terjadi lagi di masa depan. Meskipun tujuan mengingat dalam ketiga kasus ini berbeda, mereka sama-sama tidak mau melupakan hal menyakitkan yang pernah terjadi. Perubahan tren mengingat terjadi karena keterbukaan informasi di era teknologi modern. Teknologi media modern telah membawa cara baru bagi kita dalam melihat konflik. Siaran langsung sebuah pertempuran yang sedang terjadi bisa ditampilkan langsung dan disebarkan ke seluruh dunia dalam hitungan detik. Kita bisa melihat video mengenai perang yang terjadi di Suriah di tahun 2015, catatan perang dunia ke-dua, atau dokumenter rekaan mengenai perang yang terjadi di abad pertengahan. Cerita yang tidak pernah muncul dalam buku sejarah, yang biasanya ditulis oleh para pemenang, kini muncul melalui berbagai media independen. Ingataningatan saling berkompetisi. Banyak penelitian interdisipliner telah dilakukan untuk menganalisis memori. Dalam berada dalam pikiran; tidak lupa; timbul kembali dalam pikiran; menaruh perhatian; memikirkan akan; hati-hati; berwaswas; 7 mempertimbangkan (memikirkan nasib dan sebagainya); cak Kata apabila kita bandingkan remember remember (Fowler, 1995). Bahasa Indonesia menunjuk bahwa mengingat bukan hanya ketika kita memanggil sesuatu untuk kembali dalam pikiran, namun juga menyangkut peringatan dan hal yang berhubungan dengan aksi di masa yang akan datang (pertimbangan). Sementara itu, Dictionary of Philosophy and Psychology menjelaskan kata Re + memiri) in thought; to exercise memory (Baldwin, 1960). Jadi menurut arti katanya, mengingat adalah sebuah tindakan untuk memanggil kembali peristiwa yang terjadi di masa lampau ke dalam pikiran kita masa kini. Dalam kajian filoso leksikalnya. Stanford Encyclopedia of Philosophy (SED) (Sutton, 2010) memperlihatkan bahwa proses mengingat berkaitan erat dengan jenis ingatan yang hendak diperolehnya. Ingatan sendiri 7 Lihat KBBI Online, diakses 8 Februari 2013. 8 dibagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok ingatan pertama adalah ingatan non-deklaratif. Memori jenis ini tidak memerlukan pencarian kebenaran, misalnya ingatan memainkan instrumen musik, menyetir, berbicara. Kemampuan mengingat fakta mengenai suatu hal juga masuk dalam jenis ingatan proporsional ini, misalnya ulang tahun seseorang, tanggal wisuda, jadwal kuliah, dan sebagainya. Kelompok ingatan kedua adalah ingatan deklaratif. Ingatan jenis ini menuntut pencarian kebenaran akan kejadian yang terekam. Ingatan semantik juga masuk dalam ingatan deklaratif ini, di mana ingatan fakta berhubungan dengan informasi yang perlu diketahui untuk memahami apa isi dari ingatan itu, misalnya sistem apartheid di Afrika Selatan. Jenis lain adalah ingatan rekolektif atau episodik, yang berisi rekaman kejadian dan episode, seperti percakapan, pertengkaran, perasaan tentang suatu hal yang terjadi. Ingatan deklaratif meminta kita untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ingatan deklaratif dianggap juga sebagai kebutuhan dasar manusia untuk memiliki identitas diri. Seseorang akan menghadapi kesulitan jika tidak memiliki ingatan deklaratif. Mengingat dalam bentuk ini akan selalu berada dalam bentuk aktif dan dinamis. Ingatan jenis inilah yang kita bahas dalam paper ini, terutama ketika hal itu berhubungan dengan konflik yang terjadi. MENGINGAT ATAU MELUPAKAN Sebelum kita masuk ke apa yang teologi Kristen katakan mengenai ingatan, saya akan mencoba untuk menyampaikan argumen yang meyakinkan kenapa mengingat ini menjadi hal yang penting. Mengingat masa lalu dapat mengundang kembalinya rasa sakit, misalnya ingatan bagi korban perkosaan atau korban pelecehan seksual di masa kecil. Para korban ingin semua ingatan mengenai hal tersebut bisa dihapus dari hidupnya. Karena ketakutan ini, banyak orang memilih untuk melupakan dan mengubur dalam-dalam luka yang dialaminya. Ketakutan membuka luka yang sudah disimpan akan membuka luka itu membuat banyak orang memilih untuk melepaskannya. Ingatan juga dapat membawa seseorang kepada balas dendam. Masa lalu yang belum terselesaikan, dapat kembali di masa depan dan membuat kita melakukan kekerasan. Mereka yang pernah mengalami kekerasan di masa kecilnya, yang traumanya belum disembuhkan, cenderung mengulangi kekerasan itu di masa dewasanya. Dalam konteks komunal, ingatan yang diwariskan dapat membuka konflik baru di masa depan. Kekerasan bisa terjadi karena balas dendam atas suatu hal yang dilakukan komunitas lain terhadap komunitasnya, bahkan dari beberapa generasi sebelumnya, tanpa pernah mengalaminya. Dengan ingatan sebagai korban, sebuah kelompok dapat membenarkan tindakannya di masa kini untuk melakukan kekerasan terhadap kelompok lain. Ini sebabnya mengingat tidak selalu menjadi langkah yang disukai dalam menyelesaikan konflik. 9 Ingatan juga selalu memiliki banyak sisi, dan sering tidak sempurna. Cara mengingat selalu tergantung kepada siapa yang mengingatnya, usianya, latar belakangnya, pandangan religius dan politiknya, dan situasi di mana mereka mengingatnya. Ingatan ini juga bisa berubah karena waktu, pengalaman lain, dan emosi yang terlibat di dalamnya (Wollaston, 1996). Karena kesulitan dan tantangan ini, maka orang lebih memilih untuk menggunakan forgive and forget maafkan. Namun demikian, kalimat ini sekarang digunakan untuk hal lain, yaitu untuk melupakan, dengan atau tanpa proses memaafkan. Tetapi, apakah betul seseorang bisa memaafkan dan melupakan? Memaafkan bukan melupakan, demikian juga sebaliknya. Kita tidak bisa memaafkan hal yang sudah kita lupakan, dan kita biasanya tidak bisa melupakan hal yang begitu menyakitkan meskipun kita sudah memaafkannya. Ketika kita melupakan sebuah peristiwa, maka kita tidak perlu memaafkannya, karena tidak ada hal yang diingat untuk dimaafkan. Kita hanya bisa memaafkan hal yang kita ingat. Jadi, hal pertama yang diperlukan dalam proses memaafkan adalah mengingat. Ingatan tentang detil dari apa yang terjadi tidak sama dengan ingatan tentang emosi kita. Bayangkan ketika seorang istri dilukai oleh perkataan suaminya. Sang istri bisa mengingat detil perkataan suaminya yang menyakitinya, atau dia bisa juga hanya mengingat perasaan sakit yang ditimbulkannya. Orang sering menekan ingatannya untuk melupakan kejadian yang menyakitkan. Namun demikian, yang menjadi bahaya adalah ketika emosi akan suatu kejadian tetap diingat, sementara detil kejadian sudah dilupakan. Tindakan melupakan, apalagi dalam hal kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain, tidak dianggap sebagai kemerosotan nilai moral, melainkan bagai sebuah dukungan atas tindak kejahatan itu sendiri (Schimmel, 2002: 48-49). Ketika seseorang melupakan tindak kejahatan, maka dia membenarkan kejahatan itu. Menurut Schimmel dan Wiesel, kita semua diminta untuk menjadi penerus ingatan korban sebagai tanda penolakan terhadap kejahatan yang terjadi. Karena itu, tindakan mengingat bukan saja perlu dalam proses memaafkan, namun juga untuk memutus rantai kejahatan. MENGINGAT DALAM TEOLOGI KRISTEN Setelah melihat penjelasan dan hubungan antara mengingat dan melupakan, sekarang kita akan melihat apa sebenarnya yang disebut dengan teologi mengingat dalam kekristenan? Bagaimana dia bisa membantu kita untuk mencapai rekonsiliasi? Perintah untuk mengingat sebenarnya menjadi pusat dari teologi Kristen. Orang Kristen selalu diminta untuk mengingat identitasnya, dan kuasa penyelamatan Allah dalam hidup, kematian, dan kebangkitan Kristus. Liturgi adalah respons umat terhadap ingatan ini. Alkitab juga penuh dengan perintah untuk mengingat karya Allah. Karena itu, adalah baik kalau kita bisa 10 kembali ke dasar mengingat dalam teologi, terutama kalau dihubungkan dengan konflik dan proses memaafkan.8 Hal ini menjadi penting karena mengingat adalah langkah untuk memutus lingkaran tindakan ingatan negatif, yaitu ingatan yang menyakitkan yang tidak bisa diselesaikan. dalam Perjanjian Lama, dengan Israel sebagai subjek, juga sering dihubungkan dengan kondisi Israel yang selalu memberontak, sehingga mereka perlu mengingat karya Allah.9 Dalam kitab para Nabi, kata mengingat biasanya digunakan untuk arti lain, menurut Childs, ada delapan fungsi kata mengingat dalam kitab Nabi, yaitu sebagai peringatan, makian, ejekan, perdebatan, percobaan, nubuat keselamatan, janji, dan ancaman (Childs, 1962: 49-50). Karena itu, penggunaan kata ingatlah, sebenarnya mengandung arti yang lebih dari sekedar arti dunia modern mengenai ingatlah. Apa yang Israel ingat tidak sama dengan apa yang kita pahami sebagai sejarah. Israel ketertarikannya bukan pada pengetahuan akan apa yang terjadi dalam sejarah; karena dalam sejarah, seperti yang dipastikan oleh setiap halaman Perjanjian Lama, Israel bertemu dengan Allah-nya (von Rad 1980, 13). Setiap peristiwa yang diingat akan menjadi aktual bagi generasi baru yang mengingatnya. Peristiwa di masa lampau diingat dengan pengertian yang sedemikian sehingga seolah-olah peristiwa itu kembali lagi di masa kini. Setiap perayaan ritual Israel bukan hanya menjadi perayaan akan apa yang telah terjadi, tetapi pertemuan kembali dengan Allah yang telah dan sedang menyelamatkan mereka. Kejadian yang lalu diingat seakan-akan mereka terjadi lagi di masa kini. Ketika kata ingatlah dihubungkan dengan Allah sebagai objek, maka Israel meminta Allah untuk mengingat perjanjian yang mereka adakan, di mana Allah adalah Allah Israel. Ketika permohonan untuk menolong mereka dan melepaskan mereka dari cengkeraman musuh. Ketika Allah menjadi subjek, kata mengingat berhubungan dengan kesalahan Israel dan aksi Allah dalam menghukum atau meninggalkan mereka. Kata lupa ( juga dihubungkan dengan kesalahan Israel dalam tidak mengingat perjanjiannya dengan Allah. Ketika Allah 8 Lihat karya-karya yang menjelaskan hal ini seperti L. Gregory Jones, Embodying Forgiveness: A Theological Analysis (Grand Rapids: Eerdmans, 1995); Geiko Müller-Fahrenholz, The Art of Forgiveness: Theological Reflections on Healing and Reconciliation (Geneva: WCC Publications, 1997); Gregory Baum & Harold Wells (eds.), The Reconciliation of Peoples: Challenge to the Churches (Geneva & New York: WCC & Orbis Books, 1997); Desmond Tutu, No Future without Forgiveness (New York: Doubleday, 1999); Raymond G. Helmick & Rodney L. Petersen (eds.), Forgiveness and Reconciliation: Religion, Public Policy, and Conflict Transformation (Pennsylvania: Templeton Foundation Press, 2001). Philosophers have also struggle with the issue of forgiveness and remembrance especially in the communal context, see Donald W. Shriver Jr., An Ethic For Enemies: Forgiveness in Politics (Oxford University Press, 1997); Martha Minow, Between Vengeance and Forgiveness (Boston: Beacon Press, 1998); Trudy Govier, Forgiveness and Revenge (New York: Routledge, 2002). 9 Lihat Mzm. 78; 106; Yes. 63:7; Neh. 9:16 ff. 11 memaafkan Israel, Dia tidak lagi mengingat dosa mereka (Yer. 31:34). H kepada Allah yang tidak lagi menghukum Israel. Kata utama yang digunakan untuk mengingat dalam Perjanjian Baru adalah (anamnesis). Jika Allah mengingat seseorang, maka orang itu akan memeroleh kasih dan berkat. Kata mengingat juga terhubung dengan aksi perdamaian (Mat. 5:23), dan memegang teguh Firman Allah (1Kor. 11:2). Ide mengingat yang paling utama dapat ditemukan dalam institusi Perjamuan Kudus. Perjamuan Kudus adalah sebuah kejadian yang unik, yang dilakukan oleh Yesus sendiri dan yang Dia minta untuk murid-murid lakukan sebagai peringatan akan Yesus. Mengingat kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus adalah inti dari Perjamuan Kudus. Inilah Perjanjian Baru yang merupakan kelanjutan dari Perjanjian Lama yang telah dimiliki Allah dan Israel. Bahkan Perjamuan Malam itu sendiri bukanlah sebuah tradisi baru, melainkan sebuah Perjamuan Paskah yang diberi makna baru oleh Yesus. Keselamatan masa lalu yang Allah beri kepada Israel diingat kembali, lalu diperbarui dalam keselamatan baru yang dilakukan oleh Kristus. Penyelamatan Allah akan selalu diingat dalam penyelamatan Kristus. Peringatan ini juga bukan sebuah peringatan pasif, ada karakter pengakuan dosa dan rekonsiliasi di dalamnya. Sama seperti Israel yang mengakui dosanya, Perjamuan Kudus juga menuntut sebuah pengenalan dan pengakuan diri sebagai sarana pemeriksaan sebelum kita masuk ke meja perjamuan (1Kor. 11:28, 31). Pengakuan dan pemeriksaan diri tentu menuntut tindakan mengingat apa yang telah dilakukan sebelum seseorang mengalami rekonsiliasi dengan Allah. Ada tiga teolog yang telah menyinggung tentang peringatan dalam uraian mereka. Johann Baptist Metz seorang teolog Katolik dari Jerman, Alexander Schmemann, seorang teolog Ortodoks dari Estonia, Rusia, dan Miroslav Volf seorang teolog Protestan kelahiran Kroasia dan besar di Serbia, telah membahas mengenai peran penting proses mengingat dalam teologi. Ketiga teolog ini setuju bahwa orang Kristen tidak boleh melupakan ingatan mereka sebagai umat Allah dalam perayaan Perjamuan Kudus. Perayaan ini adalah pusat dari peringatan kita dalam tradisi Kristiani. Johann Baptist Metz mengatakan bahwa inti dari teologi berasal dari ingatan yang menuntut kita, yang disebutnya sebagai dangerous memory. Dangerous memory adalah memori yang meminta kita untuk mengingat mereka yang menderita dan kemudian bertindak atasnya. Ingatan seperti ini akan menentukan ekklesiologi sebuah Gereja dan keterlibatannya di dunia (Metz, 1980: 184). Ingatan ini juga bisa menjadi basis dalam peran gereja di dunia ini. Yang dimaksud dengan dangerous adalah, of the subversive content of these memories. Remembering is one way to become detached from the 12 gh the almighty power of things as they (Metz, 1990: 157). Ingatan dapat menjadi bahaya karena dengannya kita bisa melepaskan diri dari masa kini dan melihat apa yang telah terjadi dan menyadari kenapa masa kini terjadi, dan kemudian mengambil langkah untuk masa depan. Mengingat dapat menjadi sesuatu yang berbahaya ketika dia mengubah persepsi kita mengenai masa kini dan bertindak atasnya. Ingatan fundamental orang Kristen adalah memoria passionis. Melalui memoria passionis kita mengingat kehidupan, penderitaan, kematian dan kebangkitan Kristus, dan bahwa Allah menjanjikan pembebasan dari semua penderitaan. Karena janji Allah, kita harus selalu memiliki harapan. Ingatan kita akan penderitaan, membawa kita kepada memoria resurrectionis. Metz antisipatif: dia meminta antisipasi masa depan tertentu dari manusia menciptakan sebuah masa depan di dunia bagi yang menderita, tanpa harapan, yang tertindas, yang terluka dan tak berguna (Metz, 1990: 117). Ingatan penderitaan akan membawa Gereja sebagai komunitas orang percaya untuk terlibat dalam praktik solidaritas bersama mereka yang menderita. Gereja tidak boleh tuli dari suara penderitaan yang ada di konteksnya karena cerita ini bisa disandangkan dengan ingatan penderitaan Kristus di salib. Dengan mengatakan hal ini, Metz ingin memberi tempat mengingat bagi suara-suara yang tak terdengar dalam komunitas. Kita harus memberi tempat untuk mengingat suara-suara mereka yang menderita dalam konflik, dan justru konflik itu harus diingat sebagai dasar mengingat penderitaan. Lalu bagaimana kita bisa memproses ingatan penderitaan ini? Tempat mengingat dalam tradisi kekristenan adalah di liturgi. Kontribusi Alexander Schmemann adalah bahwa dia menunjukkan kembali Perjamuan Kudus sebagai sakramen yang memiliki aspek komunal.10 Dia mengajukan kembali sentralitas dari Perjamuan Kudus dalam teologi dan liturgi, yaitu cerita kasih dan karya Allah di dalam Kristus. Dia menyebut fungsi ini sebagai pintu masuk kerajaan Allah (Schmemann, 1973: 102). Ketika ini terjadi, aksi kita sebagai bagian dari masyarakat akan terjadi. Perjamuan Kudus menghubungkan kita dengan Baptisan sebagai pintu masuk ke dalam Gereja, dan menjadi tindakan umat bersama dalam ibadah. Sebagai konsekuensi, maka Perjamuan Kudus juga dihubungkan dengan sebuah aksi bersama, mengikat kehidupan tiap 10 Alexander Dalam St. Vladimir's Seminary Quarterly no 5 (1961), p. 18. Perjamuan Kudus memang mendapatkan tempat yang sangat penting dalam teologi dan kehidupan pribadi Schmemann. Dia menulis dalam jurnal pribadi yang kemudian diterbitkan, The Eucharist reveals the Church as community--love for Christ, love in Christ--as a mission to turn each and all to Christ. The Church has no other purpose, no 'religious life' separate from the world. Otherwise the Church would become an idol...Only this presence can give meaning and value to everything in life, can refer everything to that experience and make it full Schmemann, The Journals of Father Alexander Schmemann 1973-1983, terj. Juliana Schmemann (New York: St. Vladimir's Seminary Press, 2000), catatan tanggal 17 Desember 1973. 13 individu dalam perayaan sukacita. Karena itu, larangan mengikuti Perjamuan Kudus adalah penolakan keberadaan seseorang dalam komunitas itu sendiri. Schmemann berkata, which the Church fulfilled and manifested herself as t communion, as fulfilling membership in the Church, can be termed ecclesiological. However obscured or complicated it became later, it has never been discarded; it remains forever the essential 11 Faktor komunal tidak terpisahkan dalam perayaan Perjamuan Kudus. Sebagai pusat dari teologi, Perjamuan Kudus menawarkan kesempatan sebagai tempat memproses ingatan yang penuh dengan luka konflik, yang mengikat semua anggota Tubuh Kristus. Perjamuan Kudus membuka kesempatan bagi korban dan pelaku untuk duduk bersama merayakan perjamuan Kristus. Hampir sama dengan Metz, Schmemann juga mengatakan bahwa ingatan akan Kerajaan Allah datang dengan ingatan akan salib. Ingatan kita akan misteri Kerajaan Allah akan dibuka dalam sukacita perjamuan. Pengalaman mengingat ini bukan hanya tentang hal yang terjadi di masa lalu, melainkan juga tentang masa depan yang akan diberikan Allah kepada kita. Faktor sukacita menjadi penting dalam ingatan ini, katanya Perjamuan Kudus (Schmemann, 1973: 26). sukacita yang murni karena dia tidak tergantung kepada hal apapun di dunia ini, dan bukan pula hadiah dari apa yang kita miliki. Ini betul-b ini murni bentuknya, maka sukacita ini memiliki kekuatan transformasi, satu-satunya kekuatan (Schmemann, 1973: 55). Kekuatan, sekaligus kelemahan ide Schmemann ini adalah misteri Perjamuan Kudus yang dapat mengubah Gereja untuk lebih aktif dalam konteks sekitarnya. Namun, dia tidak menjelaskan bagaimana ini bisa terjadi secara konkret. Bagaimana mungkin korban dan pelaku maju ke meja perjamuan yang sama, ketika mereka bahkan tidak berbagi cerita yang sama mengenai konflik yang mereka hadapi? Bagaimana mungkin mereka dapat berbagi ketika perdamaian ingatan mereka belum terjadi? Bagaimana cara berbagi ingatan dari perspektif yang berbeda? Di sini kita bisa menggunakan ide Miroslav Volf tentang apa yang disebutnya mengingat dengan jujur. Ada tiga alasan mengapa baik korban maupun pelaku harus mengingat dengan jujur. Pertama, ini adalah sebuah kegiatan sosial di mana ingatan korban akan memengaruhi sikapnya di masa yang akan datang terhadap lingkungan di mana mereka berada. Kedua, peringatan bisa menjadi pelajaran agar hal yang serupa tidak terjadi di masa depan. Lalu yang 11 Alexander Schmemann, http://www.schmemann.org/byhim/confessionandcommunion.html, diakses pada Oktober, 2009. 14 ketiga adalah untuk berlaku adil terhadap sang pelaku, dengan tidak menuduh mereka melakukan apa yang mereka tidak lakukan, atau membebaskan mereka dari kesalahan mereka. Karena alasan-alasan ini, mengingat dengan jujur adalah langkah penting dalam mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Menurut Volf, hanya ada satu syarat dalam nceritakan apa yang anda ingat tidak kurang dari apa yang kau ingat dan apa yang kau hendak katakan (Volf, 2006: 45). Volf sadar akan tantangan dan kesulitan dalam menemukan kebenaran dalam ingatan. Karena itu dia berpendapat bahwa itikad baik diperlukan dalam melakukan hal ini (Volf, 2006: 49). Meski kisah yang diceritakan hanya persepsi seseorang akan apa yang sesungguhnya terjadi, ketika hal ini dilakukan dengan itikad kan untuk mengingat, kita menyatakan bahwa, sampai ke usaha kita yang terbaik, ingatan kita akan suatu (Volf, 2006: 51). Kebenaran tidak bisa dipaksa dan memerlukan itikad baik dari yang mengatakannya. Bagaimana kita bisa mengetahui kebenaran dari sebuah ingatan yang tentunya berbeda dengan ingatan yang lain? Volf sadar akan kesulitan ini. Karena itu dia menyatakan bahwa keinginan untuk merangkul yang lain harus ada agar kita bisa menemukan kebenaran (Volf 1996, 258). Menurut Volf, mengingat dengan jujur adalah kewajiban moral kita. Berdasarkan teks Keluaran 20:16 dan Yakobus 5:12, Volf mengatakan bahwa seseorang tidak selalu disalahkan kalau dia lupa secara tidak sengaja, namun semua bertanggung jawab untuk mengingat dengan benar (Volf, 2006: 52). Dengan mengingat secara jujur, kita berlaku adil terhadap yang lain. Proses ini bisa kita lakukan bersama di dalam komunitas yang menjaga ingatan itu. MENGINGAT, MENGAMPUNI, DAN REKONSILIASI Apa yang sudah kita telusuri adalah kemungkinan mengingat konflik yang terjadi untuk proses perdamaian dan rekonsiliasi antara pihak yang bertikai. Rekonsiliasi sejati datang dari proses panjang yang dimulai dengan mengingat. Teologi Alkitab sudah menunjukkan bahwa rekonsiliasi berhubungan erat dengan pengampunan dan perintah untuk mengingat, dalam hal ini mengingat kesalahan, sebagai awal dari proses pengampunan. Proses mengingat ini dilakukan dalam komunitas yang siap mendengar dan mengingat mereka yang menderita. Metz menunjukkan pentingnya mendengarkan suara mereka yang menderita. Schmemann mengingatkan kembali tentang pentingnya Perjamuan Kudus dalam membangun teologi dan liturgi. Mengingat bisa dilakukan secara komunal dalam perayaan Perjamuan Kudus, dengan mengingat Kristus dan berhadapan dengan saudara semeja perjamuan. Sementara itu, Volf mengatakan bahwa mengingat harus dilakukan dengan itikad baik dan dengan kejujuran. Dengan anamnesis dalam perayaan Perjamuan Kudus, kita mengingat pelayanan dan kehidupan Kristus, juga penderitaannya, dan tawaran pengampunan dosa yang penuh dengan sukacita. 15 Dalam mengingat masa lalu yang menyakitkan, Perjamuan Kudus menawarkan jaminan bahwa ingatan itu bisa kita taruh di kaki Kristus sehingga kita terbebas darinya. Umat yang mengingat akan menjadi tempat penyimpan ingatan tersebut. Ingatan itu menjadi ingatan umat dan kita menyerahkannya kepada Allah yang mengingat kita. Penyerahan ingatan tidak berarti melupakannya. Cerita pahit yang ditanggung menjadi cerita bersama. Ingatan itu masih tetap ada, namun emosi yang dikandung di dalamnya berubah menjadi ingatan yang membebaskan. Inilah tawaran yang diberikan oleh teologi mengingat dalam Perjamuan Kudus. Melupakan bukanlah tujuan dalam mengingat, itu adalah sebuah hasil akhir dari proses panjang yang mungkin terjadi. Mengingat juga bukan quick fix yang langsung memberikan obat penyembuh kepada mereka yang melakukannya. Ini adalah langkah awal dalam jalan panjang menuju rekonsiliasi sejati. Gereja-gereja yang sudah atau sedang mengalami konflik perlu memikirkan bagaimana dia bisa mencapai rekonsiliasi sejati dalam dirinya sendiri. Rekonsiliasi bisa berjalan lambat seperti pengakuan antara Gereja Katolik Roma dan Gereja pasca-Reformasi, atau berjalan relatif cepat, atau bahkan tidak sama sekali. Sebagai umat Allah, gereja harus memikirkan proses rekonsiliasi ini dengan serius dalam dirinya sendiri.