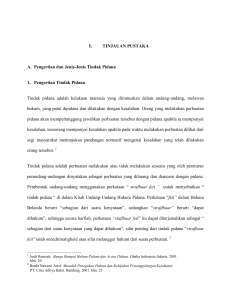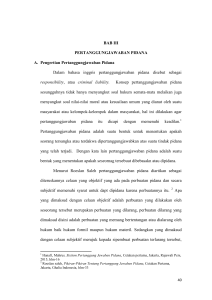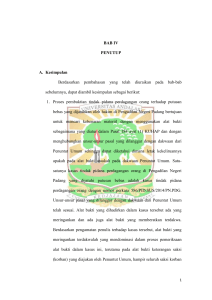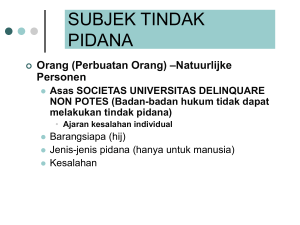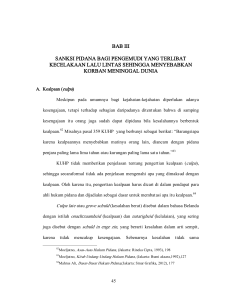negara hukum mitos dan aliran positivisme
advertisement

TANGGUNG JAWAB PIDANA DOKTER DALAM PELAYANAN KESEHATAN Oleh: Rosmala Dewi Sakti Prawira S.H., M.H 1 Abstract It is perfectly clear, that commiting a professional error has more severe consequences, which particularly consist in the fact that the trust placed in the proffesion can be hurt budly, damaging the particular professionalgroup as well as those who have made use of the professional service especially. Keywords : medical professional, medical law. A. Pendahuluan Perkembangan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan yang dicapai saat ini sudah sangat mendukung dalam bidang pengobatan internasional di dunia. Hal ini terbukti dengan terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Perkembangan ilmu dan tekhnologi di bidang kesehatan itu juga diiringi dengan perkembangan hukum di bidang kesehatan, sehingga secara bersamaan para pelaku kesehatan terutama dokter, akan menghadapi masalah hukum juga yang timbul dari kegiatan, perilaku, sikap dan kemampuannya dalam menjalankan profesi kesehatan. Bersamaan dengan isu-isu yang menuntut agar hukum memainkan perannya guna melindungui pasien dari tindakan-tindakan malpraktek yang terdengar semakin 1 Dosen Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung keras, yang membawa banyak kasus yang diangkat ke pengadilan dengan gugatan perdata atau tuntutan pidana akibat terjadinya malpraktek atau kurang memadainya pelayanan kesehatan. Untuk mengantisipasi dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat selaku pasien atau sebagai pengguna pelayanan medis dari dokter sebagai profesi pelaku kesehatan. Kemampuan untuk mengetahui dan memahami perangkat hukum yang berisi kaidah-kaidah ataupun prosedur yang berlaku di bidang kesehatan sangat diperlukan. Karena hanya dari pemahaman inilah kemajuan dari ilmu dan tehnologi kesehatan itu dapat dimanfaatkan sesuai porsinya atau dengan kata lain sebagaimanamestinya. Berdasarkan hal tersebut, penulis hendak membahas tentang Tanggung Jawab Pidana Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan. B. Peniadaan Pidana Dasar-dasar peniadaan pidana yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana yang bersifat umum dalam undang-undang (strafuitslutingsgronden) yang harus dibedakan dengan hal-hal yang menyebabkan tidak dapat dituntutnya sipembuat/sipelaku (vervolgingsuitsluitinggronden) walaupun bagi kedua-duanya sama, yang pada pada kenyataannya si pembuat tidak di pidana karena perbuatannya. Padahal yang disebutkan pertama (strafuitslutingsgronden) jaksa penuntut umum telah mengajukan surat dakwaan. Terdakwa telah diperiksa dalam sidang pengadilan, bahkan telah diajukannya Requisitoir (tuntutan) oleh Jaksa Penuntut, dan telah terbukti terwujudnya tindak pidana itu oleh si pembuat, termasuk profesi seorang dokter. Namun, karena terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak dipidananya si pembuat, majelis hakim tidak menjatuhkan pidana (veroordeling) kepadanya, melainkan menjatuhkan putusan pelepasan dari tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging). Putusan (disebut bebas) itu dijatuhkan terhadap pokok perkaranya atau terhadap tindak pidana yang didakwakan. Undang-undang tidak melarang jaksa penuntut umum untuk menghadapkan tersangka ke sidang pengadilan dalam hal adanya dasar peniadaan pidana. Berbeda pada hal yang disebutkan kedua, karena pada alasan atau dasar peniadaan penuntutan yang tidak membenarkan jaksa penuntut umum untuk mengajukan tersangka ke sidang pengadilan (menuntutnya), misalnya tanpa adanya pengaduan mengajukan juga si pembuat tindak pidana aduan ke sidang pengadilan penetapan majelis hakim akan berisi bahwa jaksa penuntut umum tidak berwenang menuntut (niet-ontvankelijk verklaring van het Openbaar Ministerie), tidak diperlukan lagi pembuktian tentang telah terwujud atau tidaknya tindak pidana itu. Artinya pokok perkara tidak perlu diperiksa oleh majelis sehingga juga tidak diputus pokok perkaranya. Majelis hanya memutus tentang tidak berwenangnya Negara (in casu jaksa Penuntut Umum) menuntut perkara itu. Tindakan yang dilakukan majelis hakim ini bukanlah vonis, tetapi berupa penetapan (beschikking) belaka. Akibat hukum dari putusan pelepasan dari tuntuan hukum dengan penetapan yang berisi penuntut umum tidak berwenang mengadili juga mengandung perbedaan yang mendasar. Karena putusan lepas dari tuntutan hukum mengenai tindak pidana yang didakwakan atau mengenai pokok perkaranya, putusan itu tunduk pada ketentuan ayat 91) Pasal 76 KUHP. Artinya, setelah putusan itu tunduk pada ketentuan ayat (1) Pasal 76 KUHP. Artinya, setelah putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap (kracht van gewijsde zaak), perbuatan itu tidak dapat lagi diajukan penuntutan kedua kalinya. Akan tetapi, terhadap penetapan yang berisi penuntut umum tidak berwenang menuntut, karena penetapan majelis hakim itu tidak tunduk pada ketentuan Pasal 76 KUHP. Ketika dasar peniadaan penuntutan itu telah ditiadakan, misalnya dalam tindak pidana aduan (delik aduan), harus telah dipenuhinya syarat pengaduan, maka terhadap pembuat, jaksa penuntut umum wajib mengajukan tuntutan ke sidang pengadilan kembali. Dalam Bab III KUHP telah menentukan tujuh dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidananya si pelaku pidana, yaitu: a. Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab si pembuat/pelaku (ontoerekeningsvatbaarheid, pasal 44 ayat 1). b. Adanya daya paksa (overmacht, pasal 48); c. Adanya pembelaan terpaksa/noodweer, pasal 49 ayat 1); d. Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodwerexes, Pasal 49 Ayat 2); e. Karena menjalankan perintah UU (Pasal 50) f. Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 Ayat 1) g. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (Pasal 51 Ayat 2). Menurut doktrin hukum pidana, tujuh hal penyebab tidak di pidananya sipembuat/pelaku dapat dibedakan menjadi dua dasar, yakni (1) atas dasar pemaaf (schulduitsluitingsgronden), yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat dan (2) atas dasar pembenar (rechtsvaardinginggronden), yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain di luar batin si pembuat). Pada umumnya, pakar hukum memasukkan ke dalam dasar maaf yaitu: a. Ketidakmampuan bertanggung jawab b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas; c. Hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik. Sementara yang selebihnya masuk ke dalam dasar pembenar, yaitu: a. Adanya daya paksa; b. Adanya pembelaan terpaksa; c. Sebab menjalankan perintah UU; d. Sebab menjalankan perintah jabatan yang sah Tidak dipidananya si pembuat karena pemaaf (fait d’excuse) walaupun perbuatannya terbukti melanggar UU yang artinya perbuatannya itu tetap bersifat melawan hukum, namun karena hilang atau hapusnya kesalahan pada diri si pembuat, perbuatannya itu tidak dipertanggungjawabkan kepadanya. Dia dimaafkan atas perbuatannya. Contohnya seorang dokter yang dipaksa untuk memberikan kadar suntikan dosis obat berlebih pada pasien. Berlainan dengan alasan pembenar, tidak dipidananya si pembuat/ pelaku, karena perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukum perbuatannya. Walaupun dalam kenyataannya perbuatan si pembuat telah memenuhi unsur tindak pidana, tetapi karena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, si pembuatnya tidak dapat dipidana. Contohnya seorang dokter yang mengambil tindakan operasi yang mendesak sebagai pertolongan terakhir tanpa persetujuan keluarga pasien walaupun pasien kemudian meninggal dunia. Ada tiga cara yang dapat digunakan dalam rangka menyelidiki keadaan jiwa si pembuat untuk menentukan apakah si pembuat berada dalam keadaan tidak mampu bertanggung jawab, yaitu:2 1) Dengan metode biologis, artinya dengan menyelidiki gejala-gejala atau keadaan yang abnormal yang kemudian dihubungkan dengan ketidakmampuan bertanggung jawab; 2) Dengan metode psikologis, artinya dengan menyelidiki ciri-ciri itu dinilai untuk menarik kesimpulan apakah orang itu mampu bertanggung jawab ataukah tidak ; 3) Dengan metode gabungan, kedua cara tersebut di atas digunakan secara bersama-sama. Di samping menyelidiki tentang gejala-gejala abnormal juga dengan meneliti ciri-ciri psikologis orang itu untuk menarik kesimpulan apakah dia mampu bertanggung jawab ataukah tidak. 2 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, RajaGrafindo, Jakarta, 2002, h.24 Cara yang sebaiknya digunakan Majelis hakim menyelidiki untuk memperoleh keyakinan yang objektif, artinya sesuainya antara keyakinan yang terbentuk dengan kebenaran materiil (sesungguhnya) tentang keadaan jiwa si pembuat itu diserahkan pada masing-masing hakim. Apabila terdapat keragu-raguan tentang keadaan jiwa si pembuat, sebagian ahli hukum, misalnya JONKERS, berpendapat bahwa hakim tidak diperkenankan menjatuhkan pidana. Akan tetapi ada juga pendapat lain, misalnya dari Pompe, yang menyatakan hakim tetap menjatuhkan pidana. Alasannya karena kemampuan bertanggung jawab pidana bukanlah merupakan bagian inti (bestanddeel) dari tindak pidana, tapi tidak mampu bertanggung jawab itu merupakan dasar peniadaan pidana.3 Apabila dihadapkan permasalahan seperti itu, penulis lebih cenderung pada pendapat Jonkers, karena apabila ada keragu-raguan mengenai berbagai hal yang menyangkut kesalahan terdakwa, keadaan keraguan itu harus menguntungkan terdakwa, dan tidak boleh merugikan terdakwa. Hal ini bersesuaian dengan hukum acara pidana. Dalam hukum acara pidana pidana, pembuktian oleh jaksa penuntut umum di sidang pengadilan diarahkan, selain pada unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, juga untuk membentuk keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa. Atas keyakinan yang dibentuk berdasarkan alat bukti (dalam Pasal 183 KUHAP sekurang-kurangnya dua alat bukti), barulah pidana dijatuhkan. Pidana dijatuhkan atas dasar minimal dua alat bukti yang ada, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana. Ketentuan ini merupakan 3 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, h. 124 asas minimal pembuktian, yang tidak boleh dilanggar oleh hakim. Dan untuk perkaraperkara pidana karena kesalahan dari profesi seorang dokter biasanya agak sulit untuk dibuktikan. C. Kesalahan dan Kelalaian Dokter I. Kesalahan dan unsur-unsurnya Kesalahan dokter timbul akibat terjadinya tindakan yang tidak sesuai atau tidak memenuhi prosedur medis yang seharusnya dilakukan. Kesalahan seperti ini dimungkinkan terjadi karena faktor kesengajaan atau kelalaian dari seorang dokter. Menurut C. Berkhouwer & L.D. Vorstman, suatu kesalahan dalam melakukan profesi bisa terjadi karena adanya tiga faktor, yaitu:4 1) Kurangnya pengetahuan 2) Kurangnya pengalaman, dan 3) Kurangnya pengertian Mengenai kesalahan dalam melaksanakan profesi, terutama profesi dokter, merupakan hal yang sangat penting karena menurut Hoekema5, bahwa: …is perfectly clear, that commiting a professional error has more severe consequences, which particularly consist in the fact that the trust placed in the proffesion can be hurt 4 Bahdar Johan Nasution, Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, h.50 Soerjono Soekanto, Hukum Disiplin Tenaga Kesehatan dan Korelasinya dengan Hukum Administrasi Negara, Djambatan, Jakarta, 1987, h. 45 5 budly, damaging the particular professionalgroup as well as those who have made use of the professional service especially. Di dalam ketentuan yang diatur dalam KUHP, kesalahan merupakan unsur dari pertanggungjawaban pidana agar dapat dipidananya seseorang. Oleh karena itu keterkaitan kesalahan dan pidana dapat terlihat jelas, karena kesalahan itu merupakan dasar untuk dapat dipidananya seseorang. Yang artinya unsur kesalahan merupakan unsur mutlak dalam penjatuhan pidana. Kesalahan akan dianggap ada, apabila dengan kesengajaan atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan atau menimbulkan keadaan-keadaan yang dilarang oleh hukum pidana dan yang dilakukan dengan bertanggung jawab. Secara teoretis yang menjadi objek dalam hukum, meliputi seluruh peristiwa hukum yang dapat menimbulkan gangguan bagi masyarakat. Menurut Poernomo; unsur melawan hukum menjadi dasar bagi suatu tindak pidana, karena selain bertentangan dengan undang-undang, termasuk pula perbuatan yang bertentangan dengan hak seseorang atau kepatutan masyarakat.6 Pengertian perbuatan melawan hukum seperti apa yang dikemukakan oleh J.B. Van Bemmelen:7 1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang. 2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang. 3. Tanpa hak atau wewenang sendiri. 6 7 Lamintang, P.A.F, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1990, h.76 Op.Cit, Soekanto, h.149 4. Bertentangan dengan hak orang lain. 5. Bertentangan dengan hukum objektif. Dalam hukum pidana terdapat dua ajaran mengenai sifat melawan hukum, yakni: ajaran melawan hukum formal dan ajaran melawan hukum materiil. Menurut ajaran melawan hukum formal, suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur-unsur dari rumusan suatu tindak pidana (delik) atau telah cocok dengan rumusan pasal yang bersangkutan. Pada ajaran melawan hukum materiil untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap suatu perbuatan tidak cukup hanya dengan melihat: apakah perbuatan itu telah memenuhi rumusan pasal tertentu dalam KUHP, melainkan perbuatan itu juga harus dilihat secara materiil. Maksudnya apakah perbuatan itu bersifat melawan hukum secara sungguh-sungguh yaitu dilakukan dengan bertanggung jawab atau tidak. Dalam ketentuan yang diatur dalam hukum pidana bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari berikut ini: 1. Kesengajaan, yang dapat dibagi menjadi: a) Kesengajaan dengan maksud, yakni di mana akibat dari perbuatan itu diharapkan timbul, atau agar peristiwa pidana itu sendiri. b) Kesengajaan dengan kesadaran sebagai suatu keharusan atau kepastian bahwa akibat dari perbuatan itu sendiri akan terjadi, atau dengan kesadaran sebagai akan terjadi, atau dengan kesadaran sebagai suatu kemungkinan saja. c) Kesengajaan bersyarat (dolus eventualis). Yang diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan diketahui akibatnya, yaitu yang mengarah pada suatu kesadaran bahwa akibat yaitu yang mengarah pada suatu kesadaran bahwa akibat yang dilarang kemungkinan besar terjadi. Menurut Sudarto (Tamba 1990:230-231): Kesengajaan bersyarat atau dolus eventualis ini disebutnya dengan teori ”apa boleh buat” sebab disini keadaan batin dari si pelaku mengalami dua hal, yaitu: 1) Akibat itu sebenarnya tidak diketahui, bahkan ia benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut 2) Akan tetapi meskipun ia tidak menghendakinya, namun apabila akibat atau keadaan itu timbul juga, apa boleh buat, keadaan itu harus diterima. Yang berati ia sadar akan resiko yang dihadapi. 2. Kealpaan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 359 KUHP Dalam kepustakaan, disebutkan bahwa untuk menetukan adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang harus memenuhi empat unsur, yaitu: 1. Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan itu bersifat melawan hukum. 2. Mampu bertanggung jawab; 3. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan; 4. Tidak adanya alasan pemaaf Unsur-unsur diatas dapat dapat dijadikan parameter untuk menentukan ada tidaknya kesalahan dokter dalam melakukan perawatan. II. Kelalaian dan Unsur-unsurnya Kelalaian menurut hukum pidana terbagi dua macam, Pertama, ”kealpaan perbuatan”, maksudnya ialah apabila hanya dengan melakukan perbuatannya itu sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP. Kedua, ”Kealpaan akibat”, Kealpaan akibat ini baru merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain seperti yang diatur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHP. Dalam pelayanan kesehatan, kelalaian yang timbul dari tindakan seorang dokter adalah ”kelalaian akibat” Oleh karena itu yang dipidana adalah penyebab dari timbulnya akibat, misalnya tindakan seorang dokter yang menyebabkan cacat atau matinya orang yang berada dalam perawatannya, sehingga perbuatan tersebut dapat dicelakan kepadanya, yang terlebih dahulu harus dicari dulu sebab terjadinya peristiwa pidananya. D. Tanggung Jawab Pidana Dalam Pelayanan Kesehatan Hukum pidana menganut asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan”, yang selanjutnya disebutkan dalam Pasal 2 KUHP di sebutkan, “Ketentuan pidana dalam dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia”. Perumusan pasal ini menentukan bahwa setiap orang berada dalam wilayah hukum Indonesia, dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya atas kesalahan yang dibuatnya. Berdasarkan pada ketentuan itu, profesi dokter tidak terlepas dari ketentuan pasal tersebut. Apalagi seorang dokter dalam pekerjaannya sehari-hari selalu berkecimpung dengan perbuatan yang diatur dalam KUHP. Meskipun hukum pidana mengenal adanya penghapusan pidana dalam pelayanan kesehatan, yaitu: alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimanan halnya yang terdapat di dalam yurisprudensi, namun tidak serta merta alasan pembenar dan pemaaf tersebut menghapus suatu tindak pidana bagi profesi dokter. Salah satu yurisprudensi yang memuat alasan pembenar dan alasan Pemaaf dalam pelayanan kesehatan adalah (Soekanto dan Muhammad, 1983:75): Yurisprudensi dalam kasus “Natanson V. Klien tahun 1960”, Yurisprudensi ini berisi “Persetujuan (Informed Consent)” sebagai peniadaan pidana. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa profesi dokter dibebaskan dari segala tanggung jawab pidana, sebab alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi tindakan dokter, hanya terdapat pada pengecualian-pengecualian tertentu seperti ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Dalam ketentuan ini tenaga kesehatan dibenarkan melakukan abortus berdasarkan indikasi medis untuk menyelamatkan ibu hamil. Berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana maupun dari yurisprudensi, telah mengakui adanya alasan penghapus pidana yang tidak terulis. Perkembangan ini merupakan ketentuan hukum yang hidup, oleh karenanya dapat dikualifikasikan sebagai suatu alasan penghapusan pidana yang tidak tertulis. Perkembangan pertama yang mengakui adanya alasan penghapusan pidana yang tidak tertulis sejak adanya pengakuan Hoge Raad pada tahun 1916 tentang afwezigheid van alleschuld (avas), yang berarti tiada pidana tanpa kesalahan, atau yang terkenal dengan adagium geen straf zonder schuld (Senoadji, 1985: 82) Di Indonesia terdapat pengakuan terhadap ajaran melanggar hukum materiil, melalui putusan Mahkamah Agung RI No.42K/Kr/1965 tanggal 8 januari 1966 dan Putusan mahkamah Agung No.81K/ Kr/ 1973 tanggal 30 maret 1977, hal itu dipandang sebagai alasan penghapusan pidana, khususnya alasan pembenaran yang bersifat tidak tertulis. Isi putusan tersebut pada dasarnya sebagai berikut:8 1. Putusan Mahkamah Agung R.I. No.42K/kr/1965 Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum, bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan dan asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum; 2. Putusan Mahkamah Agung R.I. no. 81/Kr/1973 8 Op.Cit Bahder Johan Nasution, h.75 Asas materiele wederrechtelijkeid merupakan buitenwettelijkheid uitsluitingsgrond dan sebagai suatu alasan buitenwette-lijk sifatnya merupakan fait d’excuse yang tidak terulis, seperti dirumuskan oleh doktrin dan yurisprudensi. Sesuai dengan pendapat Moeljatno, membagi alasan penghapusan pidana menjadi alasan pembenar dan alasan pemaaf. Pada alasan pembenar, yang dihapus adalah sifat “melanggar hukum” dari suatu perbuatan, sehingga yang dilakukan oleh terdakwa menjadi suatu perbuatan yang patut dan benar. Pada alasan pemaaf yang dihapus adalah kesalahan terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap dipandang sebagai perbuatan yang melanggra hukum, akan tetapi tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.9 Dari yurisprudensi tersebut, terlihat adanya alasan penghapusan pidana bagi tindakan yang dilakukan oleh dokter, yaitu alasan penghapus pidana yang berada di luar UU. Dengan demikian bagi seorang dokter yang melakukan perawatan, jika terjadi penyimpangan terhadap suatu kaidah pidana, sepanjang dokter yang bersangkutan melakukannya dengan memenuhi standar profesi dan standar kehatihatian, dokter saja kepadanya tidak dikenakan suatu pidana, jika memang terdapat alasan yang khusus untuk itu, yaitu alasan penghapus pidana. C.Berkhouwer S dan D. Vortman menyebutkan: Seorang dokter dapat dikatakan melakukan kesalahan professional apabila dia tidak memeriksa, tidak menilai, tidak berbuat atau tidak meninggalkan hal-hal yang akan diperiksa, dinilai, 9 Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1983, h. 137 diperbuat atau ditinggalkan oleh para dokter pada umumnya di dalam situasi yang sama.10 Dari rumusan pendapat C. Berkhouwer S dan d. Vortman di atas, melihat bahwa unsur kehati-hatian dalam melaksanakan profesi kesehatan sangat penting. Dalam berbagai yurisprudensi ditentukan bahwa unsur kehati-hatian merupakan dasar untuk menentukan terjadinya kesalahan dokter. Dalam segala kinerjanya, profesi dokter dalam melaksanakan perawatan memang dituntut untuk bekerja berdasarkan pada pengetahuan dan pengalamannya, dengan tetap terikat pada syarat-syarat yang telah ditentukan. Meskipun pada akhirnya hasil akhirnya terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Karena dokter juga adalah seorang manusia biasa dengan keterbatasan yang keberadaannya tidak sepenuhnya benar-benar kita harapkan, karena terkadang keadaan yang ada diluar pengetahuannya. Seorang dokter yang melakukan perawatan hampir selalu menghadapi risiko. Menurut J. Guwandi, risiko yang dihadapi dokter dalam melakukan perawatan dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu: kecelakaan (accident), tindakan medis (risk of treatment), salah penilaian (error of judgement).11 Resiko yang ada merupakan hal-hal yang pasti akan ditemui profesi dokter, baik tindakan diagnosa maupun terapeutiknya. Apabila tindakan tersebut telah 10 Loc. Cit. Bahder Johan Nasution, h.76 Koeswadi, Hermien Hadiati, Hukum dan Masalah Medik, Airlangga University Press, surabaya, 1984, h.15 11 dilakukan dengan hati-hati, teliti dan sudah bertdasarkan standar profesi medis, hal dapat menjadi pertimbangan bahwa tindakan dokter itu tidak dapat dipersalahakan. Kesalahan dokter, biasanya berkenaan dengan hak dan kewajiban kedua belah pihak yang terikat dalam transaksi terapeutik, yaitu pasien dan dokter, yang meliputi: 1) Masalah informasi yang diterima oleh pasien sebelum dia memberikan persetujuan untuk menerima perawatan; 2) Masalah persetujuan tindakan medis akan dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan; 3) Masalah kehati-hatian dokter atau tenaga kesehatan yang melaksanakan perawatan Permasalahan pokok dalam kerangka hukum kesehatan yang pada garis besarnya mengatur dua persoalan yang mendasar, yaitu: Standar Pelayanan Medis (standard of care) yang pada pokoknya membicarakan kewajiban-kewajiban dokter. Dan standar profesi medis (Standard of Profession) yang timbul karena adanya dasar kealpaan berbentuk: kewajiban; pelanggaran kewajiban; penyebab; kerugian. Pada dasarnya seorang dokter baru dimintakan pertanggungjawabannya dimuka pengadilan kalau sudah timbulnya kerugian bagi pasien. Kerugian itu timbul akibat adanya pelanggaran kewajiban di mana sebelumnya telah dibuat suatu persetujuan. Sekalipun kewajiban dokter itu tidak secara rinci dimuat dalam kontrak terapeutik, namun kewajiban seorang dokter sudah tercakup dalam standar pelayanan medis. Sedangkan standar pelayanan medis itu dibuat berdasarkan hak dan kewajiban dokter, baik yang diatur dalam kode etik maupun yang diatur dalam perundang-undangan. Dalam Pasal 53 ayat 2 UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien. Hak-hak pasien yang dimaksudkan di sini antara lain adalah hak memperoleh informasi, hak memberikan persetujuan, hak atas rahasia kedokteran dan hak atas pendapat kedua. Hak informasi di sini dapat diartikan sebagai hak untuk memperoleh informasi mengenai semua tindakan medis serta akibatnya, baik informasi itu diberikan secara lisan maupun secara tertulis. Secara luas informasi medis dapat diartikan sebagai hal ikhwal yang menyangkut tindakan medis yang akan diambil atas diri pasien. Tentang pentingnya hak atas informasi ini dikemukakan oleh Koeswadji, sebagai berikut:”…tidak mungkin seseorang memberikan persetujuannya untuk dirawat (atau dirawat lebih lanjut) bila tidak berdasarkan pada informasi yang lengkap mengenai segala aspek serta kemungkinan akibat (dampak) perawatan yang akan dideritanya untuk dapat dan mampu mengambil keputusan mengenai hidup dan kehidupan selanjutnya. Persetujuan (untuk perawatan) tanpa ada informasi (mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penyakitanya) tidaklah sah menurut hukum.12 12 Ibid, h.57 Hak selanjutnya adalah hak persetujuan, dalam ilmu hukum kesehatan hak ini dikenal dengan istilah Informed Consent. Munculnya hak (consent) apabila didahului dengan penjelasan dan pemberitahuan (informed) tentang tindakan medis yang akan diambil, mengapa tindakan harus diambil dan apa hasilnya maupun kemungkinanan efeknya bagi pasien. Semua keterangan yang diberikan harus jelas dan dapat dimengerti oleh pasien, sehingga dengan kesadarannya sendiri pasien akan memberikan persetujuan tindakan medis. Dengan demikian “persetujuan” merupakan dasar bagi pembenaran dilakukannya salah satu tindakan terapeutik tertentu, persetujuan baik yang diberikan secara tertulis maupun diam-diam mempunyai arti dalam pandangan hukum. Dalam kaitannya dengan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, persetujuan/rekam medik menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan gugatan ganti rugi langsung tanpa melalui prosedur pidana menghadapi banyak kendala, seperti kesulitan memperoleh bukti-bukti baik oleh pasien maupun oleh keluarganya. Sedangkan untuk perkara pidana dalam membuktikan adanya culpa lata bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah bagi penuntut umum. Dalam kondisi seperti ini, sesuai dengan hukum pembuktian dalam perkara pidana Pasal 184 KUHP tentang Alat Bukti, maka persetujuan/rekam medik sangat menentukan, karena dari rekam medik dan atau consent yang diajukan sebagai alat bukti dapat diketahui terapi apa yang dilakukan terhadap pasien. Apakah sudah sesuai dengan standar profesi atau belum? Dari consent dapat pula diketahui apakah dalam melakukan diagnosa atau terapi medis, dokter sudah bekerja sesuai dengan apa yang disetujui pasien. Sehingga dengan demikian, hakim dapat menentukan apakah dokter dapat dipersalahkan atau tidak. Sejalan dengan itu Koeswadji (1992:146) menyebutkan: Salah satu jalan reliable untuk menyakinkan bahwa setiap orang memperhatikan apa yang diinformasikan secara lengkap dan akurat mengenai pelayanan kesehatan ini ialah dengan cara membuat rekaman tertulis. Suatu rekam medik kesehatan yang baik membantu perawatan pasien secara professional, di samping memberikan refleksi mengenai kualitas, mutu, derajat perawatan atau pelayanan kesehatan, rekam medik yang tertulis itu mertupakan kunci dalam suatu proses peradilan baik perdata maupun pidana, yang berkenaan dengan standar pelayanan medis dan standar profesi yang bertujuan untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan dokter. Mengenai masalah kelalaian dokter terhadap pasien, di Indonesia belum ada putusan Mahkamah Agung mengenai hukuman terhadap dokter yang melakukan kelalaian. Dengan diundangkannya UU No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, maka ancaman pidana terhadap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter yang mengakibatkan pasien menderita cacat atau luka-luka, tidak lagi semata-mata mengacu pada ketentuan Pasal 359, 360 dan 361 KUHP, karena di dalam UU kesehatan sendiri telah merumuskan ancaman pidananya. Ancaman tersebut dimuat dalam Pasal 82 UU No.23 Tahun1992 tentang Kesehatan pada Ayat 1 huruf (a) disebutkan…barang siapa yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pengobatan dan atau perawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 Ayat (4)…dipidana dengan penjara paling lama lima tahun dan atau pidana denda paling banyak seratus juta rupiah. Ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 32 Ayat (4) di ats, bermaksud untuk melindungi pasien dari tindakan dokter yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan, untuk melakukan perawatan sehingga menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi pasien. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal tersebut diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan maksud Pasal 82 UU No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, apabila pasien menderita cacat hukumannya ditambah seperempat dan apabila meninggal dunia hukumannya ditambah sepertiganya. E. Penutup Bertolak belakang dengan peristiwa-peristiwa hukum kesehatan Internasional yang banyak menggunakan yurisprudensi, di Indonesia belum banyak perkara-perkara tentang kesehatan yang menyangkut kesalahan dokter yang diputus oleh Mahkamah Agung RI. Yang diharapkan apabila dikemudian hari timbul masalah-masalah seperti ini, sangat perlu untuk mengadakan perbandingan ilmu hukum dengan Negara lain yang pernah menangani perkara hukum yang sama dengan yurisprudensi-yurisprudensinya, terutama di bidang kesehatan karena kelalaian dan kesalahan dokter terhadap pasiennya, yang bertujuan agar dapat diperoleh pemecahan masalah hukum secara adil dan tepat. DAFTAR PUSTAKA Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, RajaGrafindo, Jakarta, 2002 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1991 Bahdar Johan Nasution, Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2005 Koeswadi, Hermien Hadiati, Hukum dan Masalah Medik, Airlangga University Press, Surabaya. Lamintang, P.A.F, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1990. Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1983. Soerjono Soekanto, Hukum Disiplin Tenaga Kesehatan dan Korelasinya dengan Hukum Administrasi Negara, Djambatan, Jakarta, 1987 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran