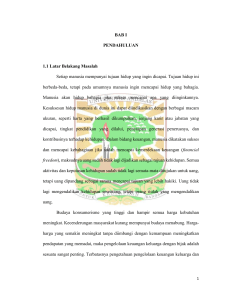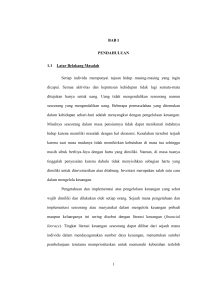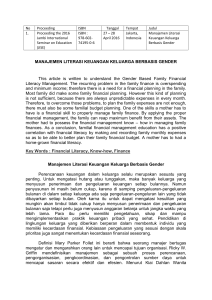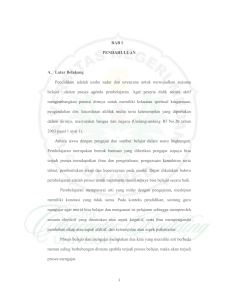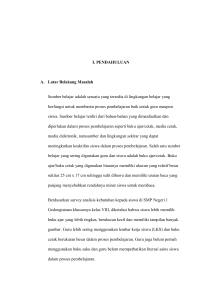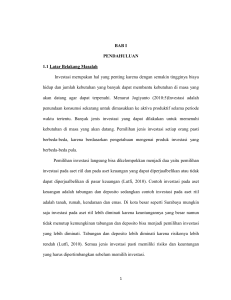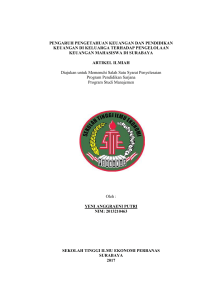LITERASI: Sebuah - Perpustakaan UNP
advertisement

LITERASI: Sebuah Tinjauan Kepustakaan Oleh Januarisdi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang 2014 Abstrak Literasi yang selama ini difahami dangkal sebagai kemampuan membaca dan menulis ternyata telah melahirkan dampak serius terhadap kegemaran dan budaya baca. Dengan anggapan bahwa seseorang yang telah mengenal huruf (melek huruf) dan pandai menggabungkannya menjadi kata, frasa dan kalimat telah terlepas dari persoalan kebutahurufan/ kebutaaksaraan (illetaracy), kita telah terjerumus kedalam persoalan kronis, rendahnya tingkat kegemaran membaca dan tidak tumbuhnya budaya baca. Tulisan ini adalah tinjauan (review) terhadap berbagai literatur tentang literasi, baik buku, artikel ilmiah, maupun laporan penelitian. Tulisan ini bertujuan memberikan wawasan tentang literasi, dengan harapan muncul pikiran dan gagasan tentang bagaimana kita seharusny mencari solusi terkit rendahnya kegemaran membaca bangsa Indonesia. Disamping membahas tentang hakikat literasi dari perspektif ilmu psikologi dan ilmu sosial, tulisan ini juga mengangkat topik emergent literacy (literasi dini) dan Information Liteacy (Literasi Informasi). 1. Pendahuluan Walaupun istilah literasi (literacy) sudah tidak asing lagi bagi kalangan masyarakat kita, khususnya para akademisi, pemahaman tentang literasi masih sangat beragam. Ada yang melihat literasi sebagai sebuah konsep yang dikaitkan dengan kemampuan baca‐tulis, ada yang melihat literasi sebagai konsep yang terkait dengan proses kognitif, ada yang melihat literasi sebagai sebuah konsep yang terkait dengan aspek sosial, ada yang mengaitkan literasi dengan ilmu perpustakaan dan informasi, ada yang melihat literasi sebagi konsep ilmu kebahasaan, dan ada pula yang melihat literasi sebagai aspek berhubungan dengan konsep pendidikan dan pembelajaran. Padangan‐pandangan tersebut tidak patut disalahkan bila kita menyadari bahwa masing‐masing pakar melihat dari perspektif bidang ilmunya masing‐masing. Akibatnya, terdapat rentangan keragaman definisi literasi yang sangat luas. Peter Roberts, seorang guru besar pada Education Department, University of Auckland, New Zealand, pada tahun 1995 mengungkapkan bahwa selama lima puluh tahun terakhir telah terdapat ratusan definisi literasi yang membuat kesulitan bagai pembuat 2 kebijakan dan praktisi memahami definisi yang paling tepat untuk kebutuhan mereka. Rentangan diantara definisi ‘literacy’ dan ‘illiteracy’ sangat berkembang dalam kurun waktu setengah abad tersebut, namun tidak ada kesepakatan diantara para pakar apa yang sesungguhnya yang dimakasudkan dengan terminologi tersebut (Roberts, 1995). Konsepsi awam dan definisi dari kamus masih memberikan ruang ambiguitas yang sangat lebar. Keadaan ini dimanfaatkan oleh para politisi, khsusnya di negara yang sedang berkembang untuk mengklaim prestasi mereka dalam mengentaskan kebutaaksaraan (illetaracy), yang mengakibatkan standar literasi kelihatan semakin menurun. Keadaan ini menginspirasikan Robert untuk melahirkan judul karyanya “Defining Literacy: Paradise, Nightmare or Red Herring?” yang diterbitkan oleh British Journal of Educational Studies, Vol. 43, No. 4 (Dec., 1995), pp. 412‐43. Sebagai usaha untuk keluar dari kerancuan pemahaman tentang literasi, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerhati, ilmuan, pakar, asosiasi dan organisasi profesi untuk melahirkan definisi istilah tersebut. Scribner (1984) berusaha meluruskan pemahaman tentang literasi dengan melihat konsep literasi dari tiga perspektif, yang disebutnya sebagai Literacy in Three Metophors (Literasi dalam Tiga Metapfora). Robert (1995) menggunakan tiga pendekatan dalam mendefinisikan literasi: 1) pendekatan kuantitatif, 2) pendekatan kualitatif, dan 3) pendekatan pluralis. Street dan Lefstein (2007) melakukan pemetaan bidang literasi dengan lima wilayah: 1) makna literasi dalam tradisi yang berbeda, 2) pemerolehan literasi (literacy acquisition), 3) konsekuensi literasi informasi, 4) literasi sebagai praktik sosial, dan 5) literasi‐literasi baru. Tulisan ini adalah sebuah sebuah tinjauan kepustakaan yang merupakan hasil analisis terhadap berbagai karya yang membahas tentang literasi. Sistematisasi penyajian tulisan ini 3 didasarkan pada pendekatan yang dilakukan oleh beberapa pakar yang lebih dominan membahas tentang literasi, antara lain Sylvia Scribner, City University of New York, Peter Roberts, Education Department, University of Auckland, New Zealand, dan Brian V. Street dan Adam Lefstein. Pada bagian awal tulisan ini, penulis me‐review (meninjau) berbagai definisi literasi sebagai bahan brainstroming untuk memahi hakikat literasi. Pada bagain berikutnya, tulisan ini memuat tinjauan tentang kajian dua perspektif yang berbeda: 1) literasi literasi sebagai proses kognisi, dan 2) literasi sebagai pratek sosial. Dua topik yang sedang ramai dibahas terkait konsep literasi, emergent literacy dan information literacy dibahas pada bagin akhir tulisan ini. 2. Sulitnya Mendefinisikan Literasi Secara leksikal, kata literasi didefinisian oleh beberapa kamus secara seragam— kemampuan membaca dan menulis. Webster’s New World Dictionary of American English (1988) umpamanya mendefinisikan literacy [n] sebagai “the state or quality of being literate”. Secara lebih spesifik literacy didefinisikan sebagai “a) the ability to read and write, b) knowledgeablity or capability. Sementara kata literate [adj] didefinisikan sebagai 1) able to read and write (mampu membaca dan menulis), 2) well‐educated; having or showing extensive knowledge, learning or culture (berpendidikan‐baik; memiliki atau memperlihatkan pengetahuan, pembelajaran atau kebudayaan yang ekstensif), 3) konowledgeable or capable (berpengatahuan atau mampu). Longman Dictionary of American English (2007) secara lebih sederhana mendefinisikan kata literacy [n] sebagai “the ability to read and write” (kemampuan membaca dan menulis). Sedangkan kata literate [adj] juga didefinisikan sebagai “able to read and write” (mampu membaca dan menulis) 4 berlawanan makna dengan kata illiterate. Collins Concise Dictionary (2001) mendefinisika kata literacy [n] sebagai 1 “the ability to rean and write” 2 the abilty to use language proficiently. Cambridge Dictionary of American English (2000) mendefinisikan literacy [n] sebagai “the ability to read and write”; a basic skill or knowledge of a subject. Webster’s Third New Internationa Dictionary of English Language, mendefinisilan lireracy [n] sebagi state of being literate. Sementara kata Literate [n] didefinisikan sebagai “instructed in letters; educated, able to read and write; learned or literary person; one who can read and write.” Online Encyclopedia of Britannica mejelaskan literasi sebagai berikut: literacy, capacity to communicate using inscribed, printed, or electronic signs or symbols for representing language. Literacy is customarily contrasted with orality (oral tradition), which encompasses a broad set of strategies for communicating through oral and aural media. In real world situations, however, literate and oral modes of communication coexist and interact, not only within the same culture but also within the very same individual. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/343440/literacy Namun demikian, kajian literasi ternyata tidak sesederhana apa yang didefnisikan oleh kamus secara leksikal sebagai kemampuan baca‐tulis; tidak pula sedangkal apa yang gambarkan oleh berbagai ensiklopedi sebagai tradisi yang dikontraskan dengan tradisi orasi. Literasi mencakup berbagai disiplin ilmu mulai dari psikologi, sosiologi, antropologi, pendidikan, politik, sampai linguistik. Karena hakikatnya yang multidisipliner, definisi literasi menjadi sangat bervarisasi berdasarkan sudut pandang keilmuan masing‐masing pakar yang mendefinisikannya. Akibatnya, literasi menjadi sebuah terminologi yang sangat rancu (ambigious) dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. 5 Literasi, sebagai mana dijelaskan oleh Blake dan Blake (2002), berasal dari kata litteratus (Bahasa Latin) yang bermakna “a learned person” (seorang yang terpelajar). Pada Abad Pertengahan, litteratus bermakna orang yang pandai membaca saja; kemampuan menulis tidak tercakup dalam makna terminologi tersebut karena kemampuan menulis bukan suatu yang sederhana yang bisa dimiliki oleh setiap orang. Ketrampilan menulis hanya dimiliki orang‐orang tertentu yang memiliki ketrampilan tinggi dalam menggunakan tinta dan bahan cair lainnya untuk menulis diatas bahan langka dan berharga seperti kulit domba. Pengertian litteratus mencakup kemampuan menulis disamping kemampuan membaca baru didefiniksan pada abad ke‐16. Sekarang, literasi merujuk pada membaca dan menulis tingkat rendah yang disebut juga dengan istilah “pragmatic literacy”; kemampuan membaca pada tingkat yang lebih tinggi tingkat normal sering disebut dengan istilah “cultured literacy”. Sejak pertengahan sampai akhir abad ke‐20 perdebatan konsep literasi mengalami masa yang paling hangat. Karena begitu tajamnya polemik tentang literasi, Stanovick dan Stanovick (1995) menggunakan istilah “Literacy Wars” (Perang Literasi). Kaum psikologi eksperimental melihat literasi sebagai kajian yang terkait dengan coding (pengkodean) teks yang melibatkan proses yang bersifat perseptual (phonological dan graphic), struktur kata (morphological), dan ketrampilan penulisan teknis (spelling). Dengan merujuk Stanovich (1986) dan Bryant (1990), Rasool (2002) mengungkapkan bahwa signifikansi dari perspektif ini adalah “proses kognitif yang melandasi membaca dan menulis tentang bagaimana membaca”. Bagi mereka, mengajar literasi adalah mengajarkan ketrampilan membaca dan menulis. Hasil literasi, dari perspektif ini, diukur dalam bentuk akusisi ketrampilan dan keuntungan sosial dan personal yang diperoleh dari kondisi seseorang yang literate. 6 Kemampuan membaca dan menulis dipandang sebagai hal yang sangat penting dalam meningkatkan dan mengembangkan ‘peluang hidup’ seseorang. Berbeda dari pakar psikologi eksperimental, pakar psikolinguistik menegaskan pandangan mereka bahwa ada tiga sistem bahasa yang berinteraksi dalam bahasa tulis: graphonic (pola bunyi dan huruf), sytactic (pola kalimat), dan semantic (pola makna). Pembca membangun makna pada saat membaca dengan memanggil kembali pengetahuan dan pembelajaran yang sudah pernah terjadi sebelumnya untuk memahami teks (Goodman, 1986:83‐9). Dengan tegas Goodman (1986) menekankan bahwa anak‐anak belajar membaca dengan cara membaca. Dengan demikian, sebagaimana disimpulkan oleh Rasool (2002), literasi didefinisikan dalam artian tingkat kedalaman makna yang dihasilkan dari hubungan antara orang dengan teks, strategi linguistik, dan pengetahuan budaya yang digunakan sebagai kunci untuk masuk kedalam makna yang melengket pada teks tersebut. Pengembang teori ‘New Literacy Studies’, seperti Street B. V., Barton D, Ivanic R, dan Stephen K, memfokuskan kajian mereka tentang literasi pada aspek sociocultural (sosiobudaya). Mereka melihat literasi sebagai sebuah kerangka analisis konseptual yang tidak terlepas dari kajian‐kajian sosial termasuk kajian antropologi sosial, sosiologi, dan sosioloinguistik. Mereka memasukkan kajaian tentang organisasi, sistem konseptual, struktur politik, dan proses ekonomi kedalam kajian literasi. Mereka menekankan bahwa kajian literasi adalah sebuah proses yang berlansung dalam konteks sosial dan budaya. Rasool (2002) melihat bahwa kajian tentang literasi mencakup berbagai displin ilmu sehingga literasi disebutnya sebagai sebuah bounded discourse (wacana yang saling terkait). Displin‐disiplin ilmu tersebut adalah experiemntal behavioral psychology, cognitive 7 psychology, social psychology, psycholinguisitcs, sociolingistics, dan social anthropology. Setiap disiplin ilmu tersebut memiliki fokus dan pendekatan penelitian yang berbeda‐beda sehingga masing‐masing melahirkan hakikat makna literasi yang berbeda pula. Experiemntal psychology berfokus pada individu, proses persepsi, pengetahuan logografis, kesiagaan fonologis (phonological awareness), ketrampilan menulis teknis, pendekodean teks (text decoding), literasi fungsional, dan metode instruksional. Cognitive psychology berfokus pada individu dan kelompok, dampak literasi terhadap perkembangan intelektual, dan ketrampilan berfikir abstrak. Social psychology berfokus pada kelompok masyarakat, perbedaan antara budaya oral dan literasi, ditekankan pada perkembangan kognitif dan kesadaran dalam kaitannya dengan hubungan sosial dalam dunia luar, seperti aspek ideologi dan politik. Psycholinguistics berfokus pada individu, proses membaca dan menulis, hubungan internal antara proses perseptual, sistem ortografis dan pengetahuan siswa tentang bahasa. Sosiolinguistics berfokus pada individu dan kelompok, bentuk dan fungsi yang berbeda bahasa lisan dan bahasa tulis, bilingalisme, multilingualisme, diskurse dan register subjek, dan competensi komunikasi. Sedangkan social anthropology berfokus pada kelompok orang, interpretasi konsekuensi sosial literasi, dan perubahan sosial. Scribner (1984) mengungkapkan bahwa respon para cendikiawan dan peneliti terhadap ambigutas pemahaman tentang literasi telah merambas lebih jauh ke persoalan pendefinisian dan pengukuran konsep. Walaupun upaya untuk memperkenalkan pendekatan pendefinisian terminologi “literacy” sudah banyak dilakukan dan menjadi definisi payung, kesepakatan antara para ilmuan dan peneliti ini belum kelihatan. Kontroversi definisonal ini, tendas Scribner (1984), tidak hanya memiliki signifikansi akademis, tapi juga persoalan sosial yang lebih jauh. Setiap formulasi jawaban tentang 8 pertanyaan “apa yang dimakasudkan dengan literasi” selalu mengacu ke evaluasi cakupan masalah dan tujuan yang berbeda untuk program‐program yang bertujuan membentuk masyarakat yang “literate”. Definisi literasi telah membentuk persepsi masyarakat terhadap individu yang dikategorikan “literate” dan “illiterate” atau “nonliterate”, yang pada gilirannya mempengaruhi substansi dan model program pendidikan. Kerancuan definisi ”literacy”, menurut Robert (1995), tidak hanya berdampak pada analisis dan kajian ilmiah saja, tapi juga pada kebijakan politik. Para politisi, khsususnya di negara berkembang sering menggunakan definisi yang rancu ini, dan dengan menggunakan angka‐angka statistik yang telah dimanipulasi, untuk mengelabui prestasi mereka yang sesungguhnya dalam program literasi. Pada masa itu, tidak ada definsi leterasi yang benar‐ benar akurat; yang ada hanya perdebatan untuk mendefinsikan terminologi “literate” dan “illiterate”, yang pada dasarnya bertujuan politis. Mendefinisikan literacyi kemampuan memabaca dan menulis ternyata tidak cukup menyentuh persoalan yang sesungguhnya. Pertnayaan terkait apa yang dibaca dan ditulis, berapa banyak yang dibaca dan ditulis, setingkat apa kemampuan membaca dan menulis seseorang untuk dinyatakan literate (melek huruf) masih belum terjawab. Scribner (1984) menyatakan bahwa sebagian besar tujuan upaya penjelasan makna “literacy” berdasarkan pada konsepsi literasi sebagai sebuah atribut individual. Para ilmuan menggambarkan literasi sebagai kemampuan individual; padahal, fakta yang lebih akurat adalah bahwa literasi merupakan sebuah prestasi sosial. Ia memberikan argumen bahwa idividu tanpa sistem penulisan tidak akan menjadi literate; seorang anak atau dewasa menangkap makna simbol tertulis bukan melalui interaksi personal dengan objek fisik, tapi melibatkan interaksi sosial. Literasi adalah sebuah hasil transimisi budaya. Kemampuan 9 literasi diperoleh oleh seseorang melalui partasi seseorang dalam aktivitas yang terorganisir secara sosial dengan bahasa tulis. Perbedaan sudut pandang dalam memahami makna sentral literasi mendorong Scribner untuk melihat literasi dari tiga sudut pandang—literacy in three metaphores: literasi sebagai adaptasi, literasi sebagai kekuasaan, dan literasi sebagai sebagai sebuah bentuk harga diri. Masing‐masing metafora tersebut berakar dari asumsi tersendiri tentang motivasi sosial terhadap literasi—hakikat praktik literasi yang telah ada, dan penilaian tentang praktik yang mana yang dianggap penting bagi pengembangan individu dan sosial. Dalam metafora pertama, literasi sebagai adaptasi, Scribner (1984) menempatkan literasi dalam konsep yang menekankan nilai‐nilai pragmatis sehingga seseorang bisa berahan hidup (survive) dalam sebuah lingkungan. Dalam metafora ini, pemahaman literasi dikaitkan dengan terminologi “functional literacy” (literasi fungsional), yakni tingkat profisiensi yang diperlukan untuk bisa berkinerja efektif dalam setting masyarakat tertentu. Literasi fungsional berkaitan dengan tuntutan untuk mampu berperan efektif dalam kehidupan sehari‐hari, seperti dalam pekerjaan, dalam lingkungan sosial, dalam kehidupan ekonomi dan sebagainya. Untuk efektif dalam pekerjaan sebagai seorang pengemudi, umpmanya, seseorang harus memiliki tingkat profisiensi tertentu terkait dengan peraturan dan etika berlalu lintas, dan penunjuk menjalankan kenderaan bermotor. Metafora kedua, literasi sebagai kekuasaan, menekankan hubungan antara literasi dengan prestasi kelompok atau masyarakat tertentu. Literasi dikaitkan dengan upaya mempertahankan hegemoni dan dominasi kelompok masyarakat tertentu atas kelompok yang lain yang menjadi basis partisipasi sosial dan politis. Scribner (1984) menekankan 10 bahwa pada masa kontemporer sekarang ini, ekspansi literasi sering dipandang sebagai alat bagi kelompok masyarkat miskin dan lemah secara politik untuk mengklaim posisi merka dalam pergaulan dunia. Simposium Internasional untuk Literasi yang diadakan di Persepolis Iran mendorong pemerintah di semua negara untuk mempertimbangkan literasi sebagai sebuah intrumen untuk melakukan perubahan dan liberasi umat manusia. Paulo Freire (1970) sebagaimana dikutip oleh Scribner (194) mengungkapkan bahwa pendidikan literasi menciptakan kesadaran kritis dimana masyarakat bisa menganalisis kondisi keberadaanya secara sosial dan terlibat dalam tindakan‐tindakan yang efektif untuk menjadi warga negara yang baik. Dalam metafora ketiga, literasi sebagai salvation dan sebagai sebuah bentuk harga diri, literasi dikatikan dengan fenomena yang menempatkan orang‐orang yang literate pada kehormatan tertentu. Orang yang mampu membaca dan menghafal kitab suci, seperti Bible untuk yang agana Kristen, Al‐Qur’an untuk yang beragama Islam dinilai memiliki kehormatan dan dianggap literate dan suci. Yang menarik untuk diperhatikan adalah bahwa dalam metofora ini, orang yang mampu membca kitab suici, seperti Al‐Quran, dengan pengucapan yang sempurna, bahkan menghafalnya tetap mendapat tempat terhormat dalam masyarakat tertentu, walaupun ia tidak memahami ayat‐ayata tersebut dan Bahasa Arab. Ringkasnya, dari perspektif metafora ini, literasi dipandang sebagai atribut kehormatan seseorang dalam masyarakat. Pemebrian atribut kekuasaan khusus kepada mereka yang literate sebenarnya berakar dari masa Yunani dan Romawi kuno. Plato dan Aristoteles membedakan antara “the man of letters” yang memiliki tradisi baca‐tulis dari “the man of poet” yang memiliki tradisi oral. Dalam perspektif humanisme Barat, literateness (keaksaraan) dianggap besinonim 11 dengan being cultured (berbudaya), sebuah terminologi yang digunakan untuk merujuk kepada seseorang yang bayak tahu tentang muatan dan tekhnik ilmu pegetahuan, seni, dan kemanusian karena ketrlibatan mereka secara historis. Dalam konsep literacy‐as‐a‐ state‐of‐ grace, kekuasaan dan funsionalitas literasi tidak terkait dengan parameter kekuasaan politik; orang yang literate memperoleh kebermaknaan hidup dari partisipasi intelektual, estetika, dan srpiritual yang mereka ekpresikan melalui penciptaan karya kemanuasian yang didesiminasikan melalui tulisan. Selain itu, usaha untuk memecahkan masalah kesulitan mendefinsikan literasi dilakukan oleh Robet (1995) dengan menggunakan tiga pendekatan dalam mendefinisikan literacy: pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif dan pendekatan pluralis. Dengan pendekatan kuantitatif, seseorang akan dinyatakan literate bila ia telah menepuh masa persekolah tertentu, atau telah lulus uji kemampuan membaca setingkat orang yang telah menempuh lama masa sekolah tersebut. Selain itu, pendekatan kuantitiatif menggunakan usia baca (reading ages) untuk mendefinisikan literasi. Setiap negara menentapkan tingkat usia baca yang berbeda‐beda. Ameriaka Serikat, umpanya, menentapkan usia baca kurang dari tujuh tahun; Inggris menentapkan usia baca sembilan tahun. Berbada dari itu, degan pendekatan kualitatif, pendefinisian istilah literacy tidak menggunakan angka‐angka seperti “lama masa persekolahan” dan “usia baca”, tapi menekankan pada gamabaran atau dimensi yag lebih umum terkait literasi. Umpamanya, Tuinman (1978: 299) mendefinisikan literacy sebagai kemampuan untuk berhubungan secara cerdas dengan informasi simbolik terekam secara mandiri. Harman (1987:96) mendefinikan literacy sebagai sebuah gabungan ketrampilan teknis yang memungkinkan seseorang berinteraksi dengan lingkungan tertentu dimana dia hudup dan berperan. Selain itu, Tilley (1984:13) mendefinisikan literacy sebagai 12 kompentensi yang digunakan oleh setiap orang kedalam usaha memahami dan menggunakan apa yang ia baca, dan mengungkapkan apa yang dia maksud dalam tulisannya, sehingga ia bsa terlibat secara efektif dalam aktivitas yang harus ia lakukan. Wells (1990:14) mendefinisikan literacy sebagai memiliki kemampuan untuk menggunakan berbagai jenis teks secara tepat untuk memperkuat tindakan, rasa dan pikiran dalam kontek aktivitas yang jelas. Ranema (1976:167) mendefinisikan literacy bukan sebagai memiliki ketrampilan tekhnis membaca dan menulis, tapi memulai jurney dari kesadaran primer sampai ke kesadaran kritis. Sementara itu, dengan pendekatan pluralis, literacy didefinisikan dengan berbagai format sesuai sudut pandang yang melihatnya; format yang paling dasar adalah format yang berasal multilpe mode of literacy (mode literasi berganda) seperti survival literacy, ketrampilan literasi yang diperlukan untuk survive (bertahan hidup) dalam dalam masyarakat tekhnologi medern (Shanahan, 1979), social literacy, ketrampilan berkomunikasi, dan kemampuan untuk berdialog dan serta merefleksi secara kritis dan informed action (Diehm, 1984), cultural literacy, memiliki informasi dasar yang diperlukan untuk berkembang dalam dunia modern (Hirsch, 1987, p. xiii), basic literacy, ketrampilan print‐decoding dasar minimal, functional literacy, kemampuan berinteraksi dengan tuntutan politis, legal, komersial, dan akupasional dalam kehidupan sehari‐hari, higher‐order literacy, mampu memecahkan masalah multi‐step secara mandiri, dan critical literacy, transformasi melalui refleksi, tindakan, dan desosialisasi (Shor, 1986, p. 189). Sehubungan dengan pendekatan pluralis, Rasool (2002) mengungkapkan bahwa literasi merupakan kajian yang bersifat multidimensional karena ia padang sebagai alat untuk berbagai tujuan, seperti sosial, ekonomi, ideologi dan plitik. Tujuan sosial terkait dengan praktik leterasi dalam kehidupan sehari‐hari seperti membaca untuk tujuan 13 informasi, belajar, kesenangan, rekreasi dan keagamaan. Tujuan ekonomis dapat dilihat dari hubungan ketrampilan literasi dengan pengetahuan yang diperlukan oleh seseorang dalam menjalankan tugasnya dalam dunia kerja. Tujuan politis literasi mengacu pada praktik literasi yang berlangsung didalam lingkungan dimana orang terlibat dalam berbagai peran sebagai warga negara, aktivis atau anggota masyarakat yang membuat mereka memperoleh posisi tertentu dalam hubungannya dengan dunia sosial. Tujuan idelogi literasi terkait dengan nilai, asumsi, keyakinan dan harapan yang membuat kerangka wacana literasi dalam konteks sosial tertentu. Persoalan lain yang menarik untuk ditinjau dalam hal kajian literasi adalah polemik antara penganut aliran autonomous dan multidiciplinary. Kelompok yang menganut aliran autonomous menganggap bahwa kajian literasi kajian yang terkait dengan proses kognisi berdiri sendiri. Ilmuan seperti Goddy (1987), Langer (1987), Barnes (2004), Reid (2011), Seong dkk (2011) dan Wolf (2012) adalah beberapa dari sekian banyak ilmuan yang memandang bahwa literasi adalah kajian yang hanya terkait dengan proses kognisi manusia. Sementara David Barton, Mary Halimton, Roz Ivanic, Allan Luke dan Brain V Street dan Scribner mempertahankan pandangan mereka untuk menganggap bahwa literasi adalah kajian yang bersifat multidisipliner, yang mencakup berbagai bidang kajian. 3. Literasi sebagai Proses Kognisi Salah satu disiplin ilmu yang sangat intensif membahas tenang literasi adalah psikologi, khusunya cognitive science. Berbagai penelitian dan tulisan tenang literasi yang dikaitkan dengan fungsi kognisi telah memperkaya cakrawala kajian literasi. Barnes (2004), 14 umpamanya, meneliti hubungan anatara literasi dengan kognisi pada orang tua berpendidikan baik. Dari hasil penelitian terhadap 664 orang yang berumur 65 keatas, mereka menyimpulkan bahwa literasi sangat berhubungan dengan fungsi kognitif pada semua ranah kognitif (cognitive domaints) pada orang tua berpendidikan baik. Jauh sebelum itu, Nelson dan McKenna. (1975) telah mengungkapkan bahwa kemampuan membaca kata sangat berkorelasi dengan intelegensi secara umum pada orang dewasa yang tidak dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Wolf dkk. (2012) mengungkapkan bahwa health literacy sangat berkorelasi dengan kemampuan kognitif fluid dan crystalized. Fluid ability adalah kemampuan kognitif yang terkait dengan pengolahan informasi aktif dimana pengetahuan terdahulu relatif sedikit membantu. Kemampuan kognitif ini mencakup processing speed, working memory, inductive reasoning, long‐term memory, dan prospective memory. Sementara crystalized ability (verbal ability) adalah kemampuan kognitif yang tersimpan dalam memori jangka panjang atau general backgroud knoledge. Dari hasil penelitan yang melibatkan 882 orang (berbahasa Inggris) yang berusia anatara 55 sampai 74 tahun, mereka menyimpulkan: the most common measures used in health literacy studies are detecting individual differences in cognitive abilities, which may predict one’s capacity to engage in self‐ care and achieve desirable health outcomes. Future interventions should respond to all of the cognitive demands patients face in managing health, beyond reading and numeracy. Berbeda dari apa yang selama ini fahamai, Langer (1987) melihat literasi bukan sebagi serangkain ketrampilan (skills); ia menandaskan bahwa literasi adalah sebuah aktivitas—sebuah cara berfikir. Lterasi adalah aktivitas yang dilakukan dengan sadar dan bertujuan. Orang membaca, menulis, berbicara dan befikir tentang gagasan dan informasi yang nyata dalam rangka menuangkan dan memperluas apa yang mereka ketahui, untuk 15 berkomunikasi dengan orang lain, menyajikan pendapat, dan untuk mengerti dan dimengerti. Dalam melakukan ini, mereka kadang‐kadang membaca dan menulis, kadang‐ kadang berbicara tentang apa yang mereka baca dan tulis, dan kadang‐kadang berbicara tentang ide yang menggunakan cara berfikir dan reasoning yang barangkali mereka gunakan juga pada saat mereka terlibat langsung dalam aktivitas berbasis teks secara langsung. Pertanyaan yang menarik untuk dibahas adalah “Apakah literasi mengubah cara berfikir manusia?” Dari sekian banyak pakar yang membahas tentang literasi dan kognisi, David R. Olson adalah ilmuan yang paling tegas yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan langsung antara literasi dengan perkembangan intelektual. Ia mengungkapkan bahwa tidak cukup bukti, koherensi, dan substansi yang mendukung thesis “pengaruh kognitif literasi”. Dalam buku yang yang berjudul “Literacy, Language and Learning: The Nature and Consequences of Reading and Writing” Olson menegaskan bahwa literasi tidak berpengaruh langsung terhadap perubahan intelektual dan sosial. Pada bagain Pendahuluan buku yang diedit oleh David R. Olson, Nancy Torraca, dan Angela Hilyard tersebut, Olson mengungkapkan: What matters is what people do with literacy, not what literacy does to people. Literacy does not cause a new mode of thought, but having a written record may permit people to do something they could not do before ‐ such as look back, study, interpret, and so on. Similarly, literacy does not cause social change, modernization, or industrialization. But being able to read and write may be vital to playing certain roles in an industrial society and completely irrelevant to other roles in a traditional society. Literacy is important for what it permits people to achieve their goals or to bring new goals into view. (Olson I985:15) Persoalannya adalah apa yang dilakukan orang dengan literasi, bukan apa yang dilakukan litersi terhadap orang. Literasi tidak menyebabkan mode pemikiran baru, tapi memperoleh rekord tulisan dapat membantu orang melakukan sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan sebelumnya—seperti melihat kebelakang, belajar, menafsikan, dan sebagainya. Sama dengan itu, literasi tidak menyebabkan perubahan sosial, modernisasi dan industrialisasi. Namun demikian, mampu membaca dan menulis menjadi penting utuk memaikan peran tertentu dalam 16 masyarakat industri dan sangat tidak relevan dengan peran lain dalam masyarakat tradisional. Litrasi sangat penting karena ia membantu orang mencapai tujuanya atau nenjelaskan tujuan baru mereka. (Olson I985:15) Selain Olson, Scribner dan Cole (1978) juga menolak thesis yang menyatakan bahwa literasi mempengaruhi kemapuan kognitif secara umum. Dari sebuah penelitian yang dilakukan terhadap masyarakat Vai (Liberia), mereka menyimpukan bahwa tidak ada bukti bahwa tulisan meningkatkan kemampuan mental secara umum (general mental abilities’. Diungkapkan bahwa tidak ada superioritas dalam hal memori secara umum diantara siswa yang belajar dan menghafal Al‐Qur’an; masyarakat Vai yang literate juga tidak memiliki kelibahan ketrampilan berbahasa. Ringkasnya, mereka tidak menemukan pengaruh kognitif literasi dalam pada masyarakat Vai. Namun demikian, pandangan yang meyakini bahwa literasi memiliki pengaruh yang berarti dalam kemampuan kognitif tidak sedikit. Goddy (1987) mengungkapkan bahwa perkembangan sistem penulisan yang semakin mudah (dalam arti bahan dan simbol yang digunakan) mempengaruhi semua bentuk kemajuan mayarakat. Dalam masyarakat yang mengembangkan tradisi oral, tradisi kebudayaan ditransmisikan komunikasi tatap muka sehingga perubahan muatan budaya terjadi karena proses kelupaan atau tranformasi bagian kebudayaan yang tidak perlu atau perlu dihilangkan. Sebaliknya, dalam masyarakat literasi, informasi dan kebudayaan disampaikan melalui rekord permanen, sehingga memungkin terjadi pertanyaan, proses penafsiran dan pemahaman yang memicu skeptisme atau keraguan. Keraguan ini tidak hanya dalam hal legenga masa lalu, tapi semua alam semesta secara keseluruhan. Dengan demikian tradisi intelektual logika muncul dan menjadi fenomena yang semakin berkembang. Goody (1987) menegaskan bahwa pengaruh literasi 17 seperti ini tidak hanya terjadi pada masyarakat Yunani tapi juga pada perbedaan intelektual antara masyarakat sederhana dan masyarakat kompleks. Selian itu, Akinnaso (1981) juga melihat pengaruh literasi terhadap kemampuan kognitif. Perkembangan sitem penulisan dan penyebaran literasi telah menyebabkan bermunculannya pengetahuan dan tekhnologi yang secara sistematis mempengaruhi hakikat struktur kognitif, linguistik, dan sosial yang telah ada, dan mengarah ke perkembagan secara gradual kedalam potensi kognitif dan linguistik manusia; literasi telah melahirkan struktur kognitif baru. 4. Literasi sebagai Praktek Sosial Selain dari perspektif psikologi, khususnya kajian kognisi, literasi juga banyak dibahas dari perspektif ilmu sosial. Pendekatan ini banyak dipengaruhi dan didukung oleh perspektif kajian etnografis yang berseberangan dari perpektif psikologi ekperimental yang cenderung bersifat individualis. David Barton, Mary Halimton, Roz Ivanic, Allan Luke dan Brain V Street adalah beberapa dari ilmuan yang menudukung pendekatan kajian literasi dari perpektif sosiologi dan konteks budaya. Secara umum mereka meyakini bahwa literasi adalah sebuah praktik sosial; mereka menolak model “autonomousí” literasi yang memandang masyrakat yang bertradisi literate dan bertradisi oral berbeda secara kognitif. Scribner (1984) mengeritik bahwa selama ini literasi terlalu dipandang sebagai atribut individual. Faktanya adalah bahwa literasi adalah sebuah pencaian sosial; literasi adalah sebuah hasil transimisi budaya. Seorang anak atau orang dewasa tidak menmperoleh makna simbol tulisan melalui interaksi personal dengan objek fisik yang melekat padanya. 18 Kemampuan literasi diperoleh seseorang dari partisipasi dalam aktivitas yang terorganisir secara sosial dengan bahasa tulis. Scribner menegaskan bahwa seseorang dalam masyarakat tanpa sistem tulisan tidak mungkin akan menjadi literate. Dengan demikian dapat difahami bahwa walaupun proses literasi belangsung didalam sistem kognisi seseorang, namun literasi tumbuh dan berkembanga dalam lingkungan sosial. Scribner (1984) menggambarkan literasi dalam tiga metafora: 1) literasi sebagai adaptasi, 2) literasi sebagai kekuasaan (literacy as power), dan 3) literasi sebagai state of grace (sebagai sebuah kehormatan). Dalam hal metafora pertama, literasi sebagai adaptasi, literasi dilihat sebagai konsep nilai pragmatis kehidupan manusia sehari‐hari. Literasi adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai anggota sebuah masyarakat untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Dalam menjalan kehidpan sehari‐hari, seperti pergi ke pasar, menjalankan mobil, menggunakan alat‐alat rumah tangga, bahkan menggunakan tekhnologi terkini seorang memerlukan kemampuan membaca dan memahami tulisan. Konsep literasi ini dikenal juga dengan litersi fungsional (functional litercy)—literasi yang ditekankan pada keefektifan seseorang dalam menjalankan tugasnya sehari‐hari, baik sebagai diri sendiri, anggota keluarga, dan masyarakat. Dari metafora litersi sebagai sebagai kekuasaan (literacy as power), literasi dilihat sebagai alat potensial untuk meraih dan mempertahankan hegemoni dalam kelompok sosial. Literasi adalah instrumen yang sering digunakan untuk menentukan kelas masyarakat; orang‐orang yang mampu membaca dan menulis diangap sebagai kelompok yang memiliki kelas lebih tinggi daripada kelompok yang tidak mampu membaca dan menulis. Orang‐orang yang tidak mampu membaca dan menulis akan menemui kesulitan, bahkan tidak memiliki peluang untuk mengkases kekuasaan ekonomi dan pilitik. Oleh 19 karena itu, menurut Scribner (1984), Gerakan ke arah transformasi realitas sosial muncul menjadi efektif dalam membawa semua rakyat untuk berpartisipasi dalam aktivitas literasi modern di beberapa negara di berbagai belahan dunia. Pada metafora ketiga, literasi sebagai kehormatan, kajian lierasi ditekan pada pandangan bahwa literasi sebagai suatu yang membawa kehotmatan khusus terhadap seseorang. Orang yang literate (pandai baca tulis) sering ditempatkan posisi yang lebih terhormat dari pada orang yang tidak mampu membaca dan menulis. Dalam berbagai masyarakat yang berbasis agama, kemampuan membaca dan menghafal kitap suci agama, seperti Al‐Quran, Injil, dan kita agama laiannya, selalu membawa seseorang untuk menjadi lebih terhormat. Scribner (1984) mengungkapkan bahwa Tradisi keagamaan yang lebh tua— Hebric dan Islam juga telah berperan secara tradisional dalam menghargai dan menghormati bahasa tertulis sebagai kekuasaan dan kehormatan besar. “Ini adalah sebuah kitab yang sempurna, tiada keraguan didalamnya,” sebuah kutipan ayat dalam Qur’an. Menghafal Qur’an—memasukkan kata‐kata Qur’an secara literal kedalam otak dan menjadikan ayat‐ayat tersebut menjadi bagian dirimu—secara simultan merupkan proses untuk menjadi melek (literatei) dan suci. Dalam sebuah studi, Verhoeven dan Vermeer (2006) meneliti pengaruh variasi sosio‐ budaya terhadap prestasi literasi anak‐anak kelas 3 sampai kelas 6 di Nederlands. Mereka mengumpul data dari 1091 anak‐anak asli Belanda, 753 orang anak‐anak yang berasal dari latar belakang bekas colonial Belanda, dan 580 anak‐anak yang berasal dari latar belakang Mediterranea. Hasil peneltian mereka meperlihatkan bahwa anak‐anak non‐native (tidak asli Belanda) tertinggal dari teman mereka yang native (asli Belanda) dalam semua tugas, walupun perbedaan dalam kemampuan memahami tugas‐tugas tertulisa relatif kecil. Anak‐ 20 anak yang bersal latar belakang Mediterrania mendapat skor secara signifikan rendah dari anak‐anak ex‐kolonial tugas‐tugas literasi membaca tapi relatif sama dalam tugas‐tugas decoding dan menulis. Untuk kedua kelompok anak‐anak dari asli dan non‐asli, struktur faktor latar belakang yang sama ditemukan mempengaruhi prestasi literasi mereka. Mereka menemukan bahwa tingkat dan status etnis secara konsisten menjadi faktor prediksi untuk skor Word Decoding (penafsiran kode), Literasi Membaca, dan Menulis Teks. Selain itu, status sosi‐ekonomi mempengaruhi Literasi Membaca dan variabel jenis kelamin mempengaruhi Ketrampilan menulis. 5. Emergent Literasi (Literasi Dini) Topik lain dari kajian literasi yang sangat banyak mendapat perhatian ilmuan adalah emergent literacy—literasi yang muncul secara alamiah pada anak‐anak usia dini sebelum mereka mengenal simbol‐simbol tulisan dan sebelum mereka mampu melakukan conventional reading (membaca konvensional). Konsep literasi ini telah ramai dibahas di kalangan akademisi (seperti, Alington, Oka & Paris, Stanovich, Brown, Palincsar, & Purcell) pada dekade 1980an. Pada dekade 1990an ilmuwan seperti Cunningham, Dow‐ Ehrensberger, Echols, Morrison, Smith, Stanovich, West, Zehr, masih terus mengangkat isu emergent literacy dengan penekanan dan bahsan yang semakin tajam. Bahkan pada tahu 2000an peniliti seperti Anthony, J. L., & Lonigan, C. J. masih aktif mengkaji persoalan ini. Sebagian besar penelitian tentang emergent literacy dikembangkan berdasarkan pada prinsip teoritis Vygotsky (1978) yang menyatakan bahwa anak‐anak belajar melalui mediasi orang lain yang kompeten. 21 Walaupun banyak pakar mengemukan definisi emergent literacy, penekanan mereka tidak kelihatan terlalu berbeda. Sulzby, (1989), Sulzby & Teale (1991) Teale & Sulzby (1986) menjelaskan bahwa emergent literacy meliputi ketrampilan, pengetahuan, dan sikap yang dianggap sebagai cikal bakal kemunculan dan perkembangan menuju format membaca dan menulis konvensioanl. Dari perspektif lain, emergent literacy dilihat sebagai suatu yang mengisyaratkan tidak adanya pemisahan yang jelas antara membaca dan prabaca (Lonigan, 2000). Whitehurst & Lonigan, (1998) menjelaskan bahwa terminologi “emergent literacy” telah digunkan untuk mengungkapkan bahwan gagasan terkait pemerolehan literasi dini dikontualisasikan sebagi sebuah kontinum perkembangan manusia, yang dimulai pada masa paling dini kehidupan seorang anak, dan bukan fenomen one‐or‐none yang dimulai ketika anak‐anak masuk sekolah. Emergent Literacy adalah prose perkembangan kemampuan membaca seorang anak yang berawal dari masa sebelum ia mengenal simbol‐simbol huruf. Ketika seorang anak kecil menjadikan buku sebagai mainan, memperhatikan gambar dalam buku, berprilaku seperti orang (berpura‐pura) membaca buku, dan bercerita kepada orang lain tentang isi buku, pada saat itulah emergent literacy sebenarnya sedang tumbuh. Kualitas sikap dan prilaku anak‐anak terhadap buku berkembang secara signifikan melalui interaksi sosial dengan orang lain yang dekat dengan mereka. Ilmuan banyak meniliti tentang emergent reading, seperti Doake (1985), Holdaway (1979), Otto (1991), dan Sulzby (1991), menyatakan bahwa prilaku berpura‐pura membaca adalah sebuah cara anak‐anak mengeksplorasi literasi sebagai aktivitas berbahasa yang bersifat holistik. Sebelum anak‐anak mulai memperhatikan tulisan, mereka telah mengintegrasikan pengetahuan tentang simbol alfabet kedalam sitem makna yang telah ada dalam otaknya dengan menggunakan petunjuk visual (seperti 22 gambar), dan memori mereka terhadap konteks yang pernah mereka dengar melalui bahasa naratif (Sulzby 1985). Bagi sebagian anak, langkah awal pengenalan emergent literasi berlangsung di rumah dan dipermantap di taman‐kanak dan sekolah; sementara bagi sebagian yang lain, tahap‐tahap perkembangan emergent literacy berlangsung di pusat penitipan anak atau pendidikan anak usia dini, taman‐kanak, dan sekolah, kemudian mendapat penguatan dalam lingkungan keluarga. Namun demikian, menurut Graves et.al. (2011), bagi semua anak‐anak emergent literacy adalah sebuah masa bagi mereka untuk memperoleh berbagai temuan tentang bunyi bahasa, bentuk kata, dan keguaan buku. Dalam proses ini, anak‐anak mulai mempelajari bagaimana mengingat dan mengeja kata sambil mengeksplorasi sistem alfabet. Anak‐anak mulai mempelajari tentang buku dan bagaimana buku disusun untuk mendaptkan informasi dan menikmati cerita. Terkahir, anak‐anak mulai menjelajahi pemahaman, dan belajar bagaimana memahami dan melahirkan bahasa tertulis. Dari hasil peneltiannya terhadap beberapa orang anak yang berusi anatara 2 sampai 5 tahun, Dooley (2010) melaporkan bahwa perkembangan emergent literasi pada anak usia dini melalui empat fase: 1) Fase books as prop 2) Fase Book as Invitation, 3) Fase Book as Script, dan 4) Fase Book as Text. Secara ringkas, ciri prilaku anak‐anak dan rentangan usia dimana prilaku tersebut teramati, dapat dilihat pada tabel berikut. Fase Interaksi Anak degan Buku Fase Book as Prop • • • Ciri‐ciri Buku diperlakukan seperti mainan lain seperti balok‐ balok plastik, boneka, mobil‐mobilan (seperti dilempar, didorong, dibuang, dll) Buku menyatu dengan mainan lain sebagai maian Sedikit perhatian terhadap isi buku secara topikal (yakni buku=buku) atau isi buku secara topikal dilihat sebagai buku (umpamanya buku=kereta api) Rentangan Usia Awal usia 2 sampai awal usia 3 tahun 23 Book as Invitation Book aas Script • • • • • • • Book as Text • • • • • Perhatian terhadap isi buku (terkait topik) Perhatian terhadap gambar Mengingat tulisan cetak secara terbatas Perhatian terhadap isi buku Perhatian terhadap gambar Suara dan mimik gestur baca keras intonasi, tekanan (seperti guru bermain) Menyadari tulisan cetak, tapi teks terpisah tidak bisa dibaca Gambar digunakan sebagai petunjuk menebak naskah Perhatian terhadap isi Perhatian terhadap gambar dan tulisan Konsep tulisan tercetak mulai (seperti beberapa indikasi penyebutan kata‐demi‐kata atau menunjuk kata‐demi‐ kata) Hampir membaca tulisan (hampir bisa membaca tanpa gambar, tapa beberapa bunyi awal perlu diingatkan untuk meperbaiki kesalahan. Akhir usia 2 sampai usia 3 tahun Awal usia 3 sampai 4 tahun Akhir usia 3 sampai 5 tahun Sunber: Dooley (2010) 6. Information Literacy Trend isu tentang literasi yang paling banyak mendapat perhatian kalangan pustakawan dan pakar ilmu informasi akhir‐akhir ini adalah literasi informasi (information liteacy). Berbagai negara seperti Amerika Serikta, Inggris, Autralia, India bahkan Singapura, Malaysia dan Thailand telah gencar melakukan gerakan literasi informasi di negara negara mereka masing‐masing. Berbagai model dan modul telah diperkenalkan, seperti the Big‐six, the Seven Pilar, Scope and Sequence, the Empower 8, Model Alberta, SMMMART B, dan Kuhlthau Model. Banyak tulisan, penelitian, dan kegitan seminar lokakarya, dan sejenisnya telah dilakukan di berbagai belahan dunia membahas tentang usgensi literasi informasi bagi masyarakat pasca modern (post‐modern society). Sejak pertema diperkenal oleh Patricia Breivik melalui karyanya yang berjudul Information Literacy: Revolution in the Library pada tahun 1980, isu literasi informasi mendapat perhatian dariberbagai kalangan, khsusnya ilmuan perpustakan dan informasi. 24 Sepanjang dekade 1980an, Breivik memperkenalkan model dan program literasi informasi yang sangat inspiratif dalam berbagai kesempatan seminar, lokakarya dan artikel ilmiah. Ia menandasakan bahwa, pada dasarnya, literasi informasi bukan isu yang terkait dengan pendidikan pemakai perpustakaan (library intruction), tapi lebih dekat dengan konsep proses pebelajaran, khsusnya pembelajaran sepanjang hayat (life‐long learning). Satu dekade berikutnya, pada tahun 1998, Brevick memperluas cakupan bahasannya tentang literasi informasi melalui bukunya yang berjudul Student Learning in the Information Age. Phoenix, Ariz.: American Council on Education/Oryx, 1998. Dalam buku ini ia mendefnisi ulang literasi informasi dengan memasukkan konsep pembelajaran berbasis‐sumbe (resource‐based leaarning), peneltian undergraduate, pembelajaran jasa (service learningi), dan pembelajaran berbasi –masalah (problem‐based learning). Sejauh ini, ada dua pendekatan pemahaman terhadap literasi informasi: pertama, pendekatan yang memebrikan penekanan pada disiplin ilmu kepustakawanan dan informasi, dan kedua adalah penekanan yang melihat literasi informasi sebagai inti proses pembelajaran. Pendekatan pertama mencakup lima aspek ketrampilan terkait informasi: 1) perumusan kebutuhan informasi, 2) pengidentifikasian sumber informasi, 3) penggunaan strategi pencarian informasi, 4) pemerolehan informasi, dan 5) evaluasi sumber informasi. Pendekatan kedua, yang didukung pakar ilmu informasi dan psikologi (seperti James W. Murcam dan Patricia Breivik), melihat literasi informasi sebagai proses yang dimulai dari pemerolehan data yang takterorganisasi, menjadi data yang terorganisisasi (informasi), sampai ke penciptaan pengetahuan baru (Januarisdi, 2012). 25 Secara umum literasi informasi didefinisikan oleh Humes (2003) sebagai kemampuan seseorang untuk mengakses, mengevaluasi, mengorganisasikan, dan menggunakan informasi dari berbagai sumber. Gilton (1994) secara tegas mengungkapkan bahwa literasi informasi tidak identik dengan litersi komputer (computer literacy), yang menghendaki seseorang memiliki ketrampilan menggunakan hardware dan software komputer. Literasi informasi bukan pula literasi perpustakaan (library literacy), yang menuntut seseorang trampil menggunakan koleksi dan jasa perpustakaan. Namun demikian, kedua literasi tersebut berhubungan yang sangat erat dengan litrasi informasi. Gilton menegaskan bahwa literasi informasi lebih dari sekadar kemampuan mengakses informasi dan pengetahun dengan bantuan tekhnologi; literasi informasi mencakup kualitas pengalaman belajar. Literasi informasi bukan hanya sekadar ketrampilan menelusur informasi dan menggunakan sumber‐sumber referensi, karena itu semua adalah persoalan tekhnis; literasi informasi pada dasrnya adalah tujuan sesungguhnya yang hendak dicapai oleh pelajar. Darch et al. (1997) mengimbuhkan bahwa literasi informasi menuntut kesadaran tentang bagaimana sistem informasi bekerja, hubungan dinamis antara kebutuhan informasi tertentu dengan sumber informasi dan saluran yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Owen (1996) dalam Langford (1998), mengungkapkan bahwa literasi informasi merupakan kapasitas untuk menguji berbagai gagasan karena kita memiliki kemampuan mengakses dan menggunkan informasi secara efektif. Ia kemudian memperluas cakupan literasi informasi dengan menambahkan bahwa dibalik peningkatan ketrampilan belajar dan meneliti, literasi informasi berperan memberikan kemampuan atau kekuatan (empower), menemukan dan bertindak terhadap informasi tersebut. Literasi informasi merupakan alat penguatan personal (personal empowerment) untuk semua orang, bukan hanya anak‐anak 26 sekolah dan mahsiswa; literasi informasi mencakup pembelajaran mandiri dan terarah sendiri (self‐directed learning), pembelajaran yang saling berketergantungan (interdependent learning); dan literasi informasi mencakup upaya memperkaya dan menghidupkan pembelajaran sepanjang‐hayat (life‐long learning). Secara lebih komprehensif, literasi informasi juga mencakup sikap dan integritas akademik seseorang terhadap informasi tersebut. Reed (2007) membagi literasi informasi atas empat fokus: 1) memulai dan menyelesaikan proses penelitian, 2) tekhnik penelusuran, 3) evaluasi materi yang ditemukan, dan 4) integritas akademik terhadap informasi yang digunaka. Fokus area pertama mencakup pengetahuan tentang lokasi bahan, sumber untuk memilih topik, dan kualitas bahan yang dibutuhkan. Pengetahuan dan ketrampilan yang harus dimiliki dalam area ini antara lain adalah cara menemukan topik yang hendak ditulis atau diteliti, pengetahuan tempat penelusuran jurnal dan buku, pengetahuan tentang peran layanan referensi (reference desk), pengetahuan tentang jumlah dan keragaman pangkalan data yang digunkan. Pengetahuan dan ketrampilan yang perlu dimiliki pada area fokus kedua adalah ketrampilan tekhnik penelusuran seperti penggunaan operator Boolean (AND dan OR), dan truncation (pemotongan kata), tekhnik penelusuran yang efsien, pengecekan semua pilihan untuk artikel, penemuan informasi dalam buku (seperti indeks subjeks), dan penemunan informasi bibliografis dalam buku. Pada fokus area ketiga, seseorang harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan terkait jenis terbitan, penelusuran melalui Internet, dan tinjauan sejawat (peer review). Sedangkan pada fokus area terakhir, seseorang harus mampu menyitir (membuat sitasi) secara benar, menghindari pelanggaran/ pencideraan integritas akademik, dan mengetahui sistem sitasi dan gaya penulisan bibliografi (seperti MLA dan APA). 27 Dalam format yang lebih formal, American Library Association (ALA) mendefinisikan literasi informasi sebagai serangkain kemampuan yang diperlukan oleh seseorang untuk menyadari bila informasi dibutuhkan dan memiliki kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang dibutuhkan secara efektif. Dijelaskan lebih jauh bahwa untuk menjadi information literate (melek informasi), seseorang harus mampu menyadari kapan informasi dibutuhkan dan mempunyai kemampuan menemukan, mengevaluasi, dan secra efektif menggunakan informasi yang dibutuhkan tersebut. Dengan demikian, orang yang melek informasi adalah mereka yang telah belajar bagaimana belajar. Mereka tahu bagaimana belajar karena mereka mengetahui bagaimana ilmu pengetahuan diorganisasikan, bagaimana menemukan, dan bagaimana menggunakan informasi tersebut dengan cara yang martabat. Mereka adalah orang yang siap untuk belajar sepanjang hayat, karena mereka dapat menemukan informasi yang diperlukan untuk berbagai tugas atau keputusan di tangan. Pada dasarnya literasi informasi berfungsi sebagai alat pencapaian prestasi akademik. Namun dalam konteks yang lebih luas, literasi informasi mencakup keberhasilan seseorang dalam kehiduan yang lebih luas. Prestasi akademik yang dicapai dengan dukungan literasi informasi adalah tujuan antara, bukan tujuan akhir yang sebenarnya dari sebuah kehidupan. Cyntia (1999) mengungkapkan bahwa persoalan literasi informasi bukan untuk membawa para ilmuan untuk lebih cepat mencapai tujuan akademik mereka, tapi untuk menjamin bahwa para sarjana yang dihasilkan oleh lembaga akademik bisa berfungsi dalam dunia kerja Era Informasi. Dunia kerja dalam kehiduapan sosial era informasi menuntut setiap orang untuk menjadi pelajar sepanjang hayat (life‐long learners). Dengan demikian literasi informasi bukan hanya persoalan yang terkait dengan persekolahan dan 28 perkuliahan formal, tapi terakit dengan isu kehidupan yang sebenarnya jauh lebih luas dari pada sekadar persekolahan dan perkuliahan. 7. Simpulan Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa literasi bukan kajian yang hanya terkait dengan persoalan kemampuan membaca dan menulis. Walauun penganut aliran autonomous menyakini bahwa literasi adalah kajian yang terkait dengan sistem dan proses kognisi manusia, literasi ternyata menyangkut berbagai displin ilmu seperti psikologi eksperimental, psikolinguistiks, antropilogi, sosiologi, ilmu budaya, politik, pendidikan dan ilmu informasi dan perpustakaan. Dengan demikian, secara umum kita bisa mengelompokkan kajian literasi kedalam dua perspektif: 1) perspektif kajian psikologi, dan 2) perspektif kajian sosial. Dari perpektif kajian psikologi, khsusnya cognitive science, literasi dipandang sebagai sebuah proses, atau aktivitas berfikir yang sangat kompleks. Pandangan ini menilai bahwa perkembangan literasi telah berlangsung sejak manusia lahir dan membangun sebuah garis kontinum sampai akhir khayatnya. Sementara dari perspektif kajian ilmu sosial, literasi dipandang sebagai hasil dari proses interkasi sosial. Dari perspektif ini, kita menyakini bahwa perkembangan literasi tidak pernah terlepas dari lingkungan sosial. Anak‐anak usia dini menumbuhkan dan mengembangkan emergent literacy mereka melalui interaksi dengan orang dewasa dan teman sejawatnya. 29 REFERENSI Akinnaso, F. Niyi (1981) The Consequences of Literacy in Pragmatic and Theoretical Perspectives. Anthropology & Education Quarterly, Vol. 12, No. 3 (Autumn, 1981), pp. 163‐200 URL: http://www.jstor.org/stable/3216330. dikases: 02/04/2014 23:07 Allington, R. L. (1984). Content, coverage, and contextual reading in reading groups. Journal of Reading Behavior, 16, 85—96. American Library Association Presidential Committee on Information Literacy. 1989. Final Report. Washington, DC. Barnes, Deborah E et.al (2004). The Relationship Between Literacy and Cognition in Well‐ Educated Elders The Journals of Gerontology; 59A, 4; ProQuestpg. 390 Barton, David, Halimton, dan Ivanic, Mary Roz (2000). Situated Literacy: Theorizing Reading and Writing in Context. London: Routledge. http://books.google.com/books?isbn=1134624220 Blake dan Blake (2002). Literacy and Learning: a Reference Handbook. By Brett Elizabeth Blake and Robert W. Blake. Californi: ABC‐CLIO, Inc., 2002. Brown, A. L., Palincsar, A. S., & Purcell, L. (1986). Poor readers: Teach, don't label. In U. Neisser (Ed.), The school achievement of minority children: New perspectives (pp. 105‐143). Hillsdale, NJ: Erlbaum. Collins Concise Dictionary (2001). New Delhi: HarperCollins Publishing. Darch, C., Karelse, C., and Underwood, P. 1997. Alternative Routes on the Super Highway. Independent Online‐Higher Education Review. Independent Educational Media. Doake, D. (1985). Reading‐like behavior: Its role in learning to read. In A. Jaggar & M. Smith‐ Burke (Eds.), Observing the language learner. Newark, DE & Urbana, IL: International Reading Association and National Council of Teachers of English. Dooley, Caitlin McMunn (2010). Young Children's Approaches to Books: The Emergence of Comprehension. The Reading Teacher, Vol. 64, No. 2 (OCTOBER 2010), pp. 120‐130 URL: http://www.jstor.org/stable/20780291. diakses: 25/04/2014 00:2 Doyle, Brooke Graham and Wendie Bramwell (2006). Promoting Emergent Literacy and Social‐Emotional Learning through Dialogic Reading. The Reading Teacher, Vol. 59, No. 6 (Mar., 2006), pp. 554‐564 URL: http://www.jstor.org/stable/20204388. diakses pada: 06/05/2014 23:57 Gilton, Donna (1994). A World of Difference: Preparing For Information Literacy Instruction for Diverse Groups. MultiCultural Review. V. 3 no. 3 (September, 1994) pp. 54‐62. Goody, Jack and Watt, Ian (1963). The Consequences of Literacy. Comparative Studies in Society and History, Vol. 5, No. 3 (Apr., 1963), pp. 304‐345 URL: http://www.jstor.org/stable/177651 dikses: 02/04/2014 22:54 Graves, Mechael et.al. (2011). Teaching Reading in 21th Century: Motivating All Learners. Boston: Pearson. Harman, D. (1987). Illiteracy: a National Dilemma. New York: Cambridge University Press. Holdaway, D. (1979). The Foundations of literacy. Auckland, New Zealand: Ashton Scholastic. Humes, Barbara (2003). Understanding Information Literacy. Published by the US Federal government. Nelson M.E. dan McKenna P. (1975) The use of current reading ability in the assessment of Dementia. Br J Soc Clin Psychology . vol. 14:259‐267. 30 Langer, J. A. (1987) A sociocognitive perspective on literacy. In J. A. LANGER (ed) Language, Literacy and Culture: Issues of Society and Schooling. New Jersey: Norwood. Lonigan, Christopher J., et.al. ( 2000). Development of Emergent Literacy and Early Reading Skills in Preschool Children: Evidence From a Latent‐Variable Longitudinal Study. Developmental Psychology, Vol. 36, No. 5, 596‐613 Longman Dictionary of American English (2007). Harlow, England: Pearson Education Limmited. Olson, David R. Nancy Torrance, Angela Hildyard (1985) Literacy, Language and Learning:The Nature and Consequences of Reading and Writing Cambridge University Press, http://www.books.google.com/books?isbn=0521319129 Oka, E., & Paris, S. (1986). Patterns of motivation and reading skills in underachieving children. In S. Ceci (Ed.), Handbook of cognitive, social, and neuropsychological aspects of learning disabilities (Vol. 2). Hillsdale, NJ: Erlbaum. Online Ensyclopaedia Britannica. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/343440/literacy Otto, B. (1991). Informal assessment of emergent reading behaviors through observation of assisted and independent story‐ book interactions. Paper presented at the annual meeting of the International Reading Association, Las Vegas, NV. Rassool, Naz (1999). Literacy for Sustainable Development in the Age of Information. Philadelphia: Language and Education Library. http://books.google.com/books?isbn=1853594326 Reed, M., Kinder, D. & Farnum, C. (2007) Collaboration between Librarians and Teaching Faculty to Teach Information Literacy at One Ontario University: Experiences and Outcomes” Journal of information literacy, 1 (3), http://jil.lboro.ac.uk/ojs/index.php/JIL/article/view/RA‐V1‐I3‐2007‐3. Reid, Jennifer (2011).The vowel house: a cognitive approach to vowels for literacy and speechInternational Psychogeriatrics 23:4, 593–3–601 Roberts, Peter (1995). Defining Literacy: Paradise, Nightmare or Red Herring?. British Journal of Educational Studies, Vol. 43, No. 4 pp. 412‐432 URL: http://www.jstor.org/stable/3121809 . http://www.jstor.org/stable/3121809. diakses: 02/12/2012 23:13. Seong Hye Choi et.al (2011). Validation of the Literacy Independent Cognitive Assessment. International Psychogeriatrics, 23:4, 593–3–601 Scribner, S. And Cole M (1978). Unpackaging Literacy. Social Science Information, 17 (1) 19‐ 39. Scribner, Sylvia (1984). Literacy in Three Metaphors. American Journal of Education, Vol. 93, No. 1, pp. 6‐21. URL: http://www.jstor.org/stable/1085087 Stanovich, K. E. (1988). Explaining the differences between the dyslexic and the garden‐ variety poor reader: The phonological‐core variabledifference model. Journal of Learning Disabilities, 21, 590‐612. Stanovich, K. E. (1992). Speculations on the causes and consequences of individual differences in early reading acquisition. In P. B. Gough, L. C. Ehri, & R. Treiman (Eds.), Reading acquisition (pp. 307‐342). Hillsdale, NJ: Erlbaum. Stanovich, K. E., Cunningham, A. E., & Cramer, B. B. (1984). Assessing phonological awareness in kindergarten children: Issues of task comparability. Journal of Experimental Child Psychology, 38, 175‐190. 31 Stanovich, K. E., & Siegel, L. S. (1994). Phenotypic performance profile of children with reading disabilities: A regression‐based test of the phonological‐core variable‐ difference model. Journal of Educational Psychology, 86, 24‐53. Street, Brian V. Literacy: An advanced Resource Book. New York: Routledge. Sulzby, E. (1986). Writing and reading: Signs of oral and written language organization in the young child. In W. H. Teale & E. Sulzby (Eds.), Emergent literacy: Reading and writing (pp. 50‐87). Norwood, NJ: Ablex. Sulzby, E., & Teale, W. (1991). Emergent literacy. In R. Barr, M. Kamil, P. Mosenthal, & P. Pearson (Eds.), Handbook of reading research (Vol. 2, pp. 727‐758). New York: Longman. Teale, W. H., & Sulzby, E. (Eds.). (1986). Emergent literacy: Writing and reading. Norwood, NJ: Ablex Tilley, C. M. (1984) Australian public libraries, the library association of Australia, and literacy, Australian. Journal of Adult Education, 24 (2), 13‐20. Tuinman, J. J. (1978) From the editor. Journal of Reading Behaviour, 10 (3), 229‐ 231. Verhoev, Ludo dan Vermeer, Anne (2006). Sociocultural Variation In Literacy Achievement. British Journal of Educational Studies, Vol. 54, No. 2, Pp 189‐211 Webster’s New World Dictionary of American English. Third College Edition. New York: Simon and Schuster, 1988 Wells, G. (1990) Creating the conditions to encourage literate thinking, Educational Leadership, March, 13‐17. Whitehurst, G. J., & Lonigan, C. J. (1998). Child development and emergent literacy. Child Development, 69, 848‐872. Wolf, Michael S. (2012). Literacy, Cognitive Function, and Health: Results of the LitCog Study 32