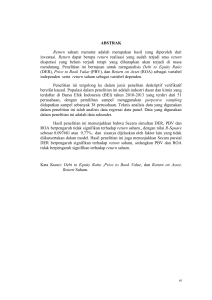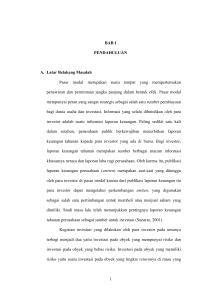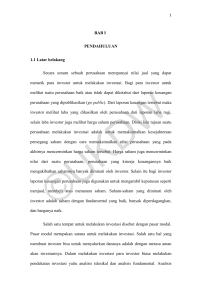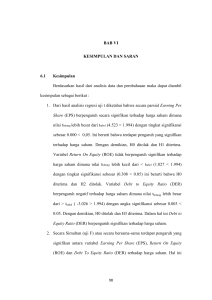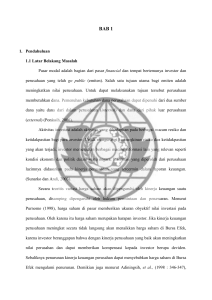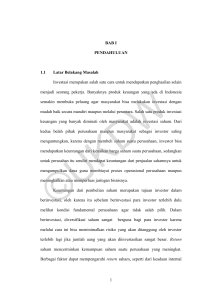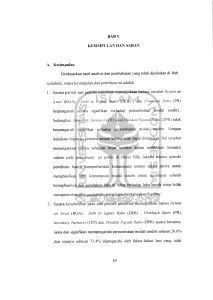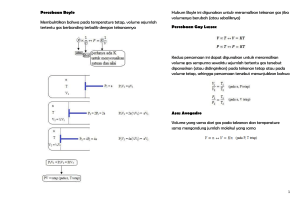PENDAHULUAN Pada tanggal 6 Juli 1823
advertisement

PEMBATALAN SEWA TANAH DI VORSTENLANDEN TAHUN 1823: KASUS KONTRA LEX REI SITAE Harto Juwono *) Abstract Land leasing is a crucial factor in history of Vorstenlanden. This phenomenon has appeared since the early XIX century. In her history, the land leasing has been stopped as Governor General G.A.G.P. Baron van der Cappelen published Staatsblad number 6 in 1823 that forbad the land leasing by Europeans in Javanese Vorstenlanden. The fact that seen as one of factors which caused Diponegoro War was a result of the application of two different legal systems: Western positive law and traditional common law. As both were applied on the same object, the subject and object would be confused and they lost a guidance for a legal action. Consequently, the conflict could not be avoided and the subject revolted against the legality of formal decision. As the decision was published, many people saw that Dutch colonial government did a breach of Javanese royal authority and his legal system. It was a reason for Javanese noblemen to support Diponegoro’s revolt against the Dutch. Key words: land leasing, Vorstenlanden, colonial legal system Abstrak Persewaan tanah menjadi bagian penting dari perkembangan sejarah di Vorstenlanden. Fenomena ini telah berlangsung sejak dekade kedua abad XIX. Sepanjang sejarahnya, proses persewaan tanah pernah dihentikan, yaitu ketika Gubernur Jenderal G.A.G.P. Baron van der Capellen mengeluarkan Staatsblad tahun 1823 no. 6 yang melarang orang-orang Eropa menyewa tanah di wilayah kekuasaan raja-raja Jawa. Peristiwa yang dianggap berperan bagi terjadinya Perang Diponegoro ini merupakan akibat dari penerapan dua sistem hukum yang berbeda pada objek dan dalam konteks yang sama, yaitu hukum positif dan hukum adat. Ketika keduanya diterapkan bersamaan di lokasi dan pada objek yang sama, baik subjek maupun objek hukum akan menjadi kabur dan kehilangan pedoman bagi pengambilan tindakan yang dianggap sah. Akibatnya, benturan tidak dapat dihindari dan mengakibatkan pengingkaran terhadap keabsahan keputusan yang diambil oleh pihak yang berwenang. Ketika keputusan pembatalan ini dikeluarkan, banyak orang menganggap pemerintah kolonial Hindia Belanda melakukan pelanggaran bukan hanya kewenangan raja Jawa melainkan juga terhadap aturan hukum yang berlaku. Pandangan itu memberikan dasar legal bagi keterlibatan banyak pemilik tanah pribumi dalam perlawanan Diponegoro. Kata kunci: sewa tanah, vorstenlanden, hukum kolonial PENDAHULUAN Pada tanggal 6 Juli 1823 Gubernur Jenderal G.A.G.Ph. Baron van der Capellen mengeluarkan sebuah peraturan yang pada prinsipnya melarang persewaan tanah oleh orang-orang Eropa di wilayah Vo r s t e n l a n d e n . L a r a n g a n i n i menimbulkan kekecewaan di antara khalayak publik, baik di antara penyewa tanah maupun pemilik tanah. Kekecewaan ini, terutama di kalangan para pemilik tanah pribumi, memuncak dalam bentuk dukungan mereka kepada Pangeran Diponegoro, yang memulai perlawanannya terhadap intervensi kolonial Belanda di Yogyakarta pada *) Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Depok. 115 Pembatalan Sewa Tanah Di Vorstenlanden Tahun 1823: Kasus Kontra Lex Rei Sitae tanggal 22 Juli 1825. Sebagai akibatnya, tim khusus yang dibentuk oleh pemerintah di Batavia untuk menyelidiki latar belakang perlawanan Diponegoro ini mengajukan laporan. Dalam laporan tersebut dikatakan bahwa faktor yang sangat menentukan terjadinya perlawanan r a k y at d i Vo r s te n l a n d e n a d a l ah pembatalan persewaan tanah, karena para bangsawan pemilik tanah yang kecewa bergerak memimpin perlawanan. Dalam historiografi Indonesia, kondisi tersebut di atas dianggap sebagai suatu kenyataan sejarah dan diakui kebenarannya sebagai bagian dari proses perlawanan Diponegoro. Hal itu terutama bisa diterima apabila pendekatan politik dan ekonomi diterapkan untuk menganalisis dan merekonstruksi peristiwa Perang Diponegoro yang berlangsung antara 1825-1830 (van den Kemp, 1897). Namun demikian, dalam telaah lebih lanjut terdapat sejumlah aspek yang perlu dicermati, khususnya bila dilihat dalam konteks yang berbeda dari pendekatan politik. Sejumlah pertanyaan dapat dilontarkan di sini, terutama menyangkut kewenangan van der Capellen mengeluarkan keputusan yang berlaku di wilayah yang tidak berada di bawah kewenangan pemerintah kolonial. Dilihat dari pendekatan hukum, dasar yang melandasi keputusan van der Capellen perlu dipertanyakan kembali, khususnya keabsahan dari penerapan kebijakan tersebut dan bagaimana relevansinya dengan konteks hukum adat yang berlaku di Kesultanan Yogyakarta. 1) Melalui pendekatan ilmu hukum, diharapkan akan diperoleh penjelasan lebih jauh dan mungkin juga simpulan yang berbeda dengan apa yang selama ini dipahami dalam historiografi Indonesia. DUALISME HUKUM Dalam menganalisis peristiwa pembatalan sewa tanah tersebut di atas, 1) harus dilihat adanya tiga pihak yang terlibat dalam hal ini. Pihak pertama adalah pemerintah kolonial sebagai pelaku pencabutan peraturan yang berdampak pada pembatalan transaksi, pihak kedua adalah pengusaha asing yang menjadi penyewa tanah, dan pihak ketiga adalah elit tradisional Jawa sebagai pemilik sekaligus pihak yang menyewakan tanah. Hubungan ketiganya memiliki posisi yang berbeda. Jika penyewa dan pemilik tanah terlibat dalam transaksi yang sah secara hukum, karena masingmasing pihak melakukan aktivitas dan transaksinya tanpa paksaan atau tekanan, dan tidak melakukan pelanggaran atas aturan hukum setempat yang digunakan, pemerintah kolonial dalam hal ini memiliki posisi yang unik. Ditinjau dari aspek hukum, posisi pemerintah kolonial seharusnya adalah yang paling lemah mengingat dalam hal ini hubungan pemerintah kolonial dan raja-raja di Vorstenlanden hanya dijalin lewat kontrak-kontrak politik. Sejak Sultan Hamengku Buwono II naik tahta di Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1792 dan juga Sultan Paku Buwono IV di Surakarta memegang kekuasaan di Kesunanan Surakarta pada tahun 1788, pemerintah kolonial di Batavia lebih banyak menggunakan kontrak politik sebagai dasar hubungan antara mereka dan kerajaan-kerajaan ini. Hal ini berbeda dengan peristiwa sebelum kekuasaan mereka yang lebih terikat dengan bentuk perjanjian (ANRI No. 258). Dalam kontrak politik, raja-raja Jawa harus mengakui dan menerima petunjuk dari Belanda dalam menjalankan kekuasaan dan pemerintahannya. Namun, pasalpasal yang dimuat di dalamnya tidak menyentuh persoalan hukum, khususnya yang berkenaan dengan tanah-tanah. Dilihat dari kondisi tersebut di atas, bisa diduga bahwa pemerintah kolonial sebenarnya hanya memiliki Persewaan tanah ini berlaku di Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta juga. Namun selain kuantitasnya, sistem dan jatuh tempo yang berlaku di Kesultanan Yogyakarta berbeda daripada di Kesunanan Surakarta sehingga menimbulkan dampak dan reaksi yang berbeda pada kedua kerajaan Jawa ini. 116 : Jurnal Ilmu Humaniora, Vol. 14, No.2 Juli - Desember 2013: 100 - 219 pengaruh dan kewenangan atas sosok raja. Pengikatan terhadap raja yang dimuat dalam kontrak-kontrak politik mereka juga dianggap sebagai ikatan hukum yang kabur mengingat dalam kontrak tersebut tidak dimuat apa konsekuensinya apabila pasal-pasal di dalamnya dilanggar, baik oleh raja-raja Jawa atau bahkan oleh Belanda sendiri. Dengan demikian, legalitas dari kontrak-kontrak tersebut lebih menekankan pada pengaturan hubungan diplomatik daripada ikatan hukum dengan segala bentuk tindakan hukum yang akan muncul sebagai akibat dari penyimpangan atau pelanggarannya. Melalui kerancuan kondisi tersebut di at as , penyelesaian hukum d i Vorstenlanden tidak bisa dilakukan kecuali dengan pendekatan politik. Setiap tindakan yang mengancam hak-hak orang Eropa dianggap sebagai pelanggaran kontrak politik meskipun tidak tercantum pasal yang jelas di situ. Hukuman yang diterapkan ditentukan menurut aturan hukum Eropa walaupun ketentuan hukum yang digunakan tidak ditegaskan. Misalnya kasus perlawanan dan akhirnya pembunuhan terhadap Raden Ronggo Prawirodirjo, Adipati Mancanegara Wetan, pada bulan Desember 1810 dan diikuti dengan penurunan Sultan Hamengku Buwono II dari tahta pada bulan yang sama dan sekali lagi pada bulan Juni 1812 menunjukkan bahwa hukum yang dipakai pemerintah Eropa adalah kontrak politik (Adams, 1931: 230). Di samping sifat kabur dalam sistem yuridis formal tersebut di atas, baik pada ketentuan pasal-pasal kontrak maupun pelaksanaannya, kontrak politik juga memiliki kelemahan hukum ketika diterapkan pada bidang per data, khususnya di sektor agrobisnis. Selain aneksasi agraria yang mewarnai kontrakkontrak politik pada awal abad XIX, khususnya kontrak bulan Januari 1811 dan Agustus 1812, tidak ada ketentuan yang mengatur aspek perdata dalam kontrakkontrak tersebut. Dengan demikian, secara de facto penguasa kolonial Eropa mengakui keabsahan aturan hukum yang 117 dibuat dan diberlakukan pada wilayah Vorstenlanden oleh raja-raja Jawa. Ketika hubungan antara penguasa Eropa dan raja-raja Jawa masih terbatas pada aspek politik dan kekuasaan, persoalan perdata tidak menjadi masalah yang rumit. Kondisi ini berubah ketika intervensi ekonomi mulai muncul akibat aktivitas niaga para pemilik modal Eropa di wilayah Vorstenlanden pada awal tahun 1820-an. Pengakuan secara de facto terhadap situasi yang ada telah mengarah pada prinsip Lex Rei Sitae. Untuk memahaminya, konsep berikut ini memberikan penjelasan, The traditional conflict of laws rule for determining the enforceability of a transfer of property or a pledge of securities effected in the direct holding system is the lex rei sitae. Under the rule, the validity of the transfer is determined by the law of the place where the security is located. The principle was first applied to immovables and those movables which by their origin belong to the territory (Bernasconi, 2007: 76). Konflik kewenangan hukum tradisional untuk menentukan pemberlakuan pengalihan hak kekayaan atau janji jaminan yang muncul dalam sistem kepemilikan langsung disebut lex rei sitae. Dalam aturan ini, keabsahan pengalihan hak ditentukan oleh hukum di tempat jaminan berada. Prinsip ini pada mulanya berlaku bagi barang yang tidak bergerak dan kemudian barang bergerak menurut asal-usul wilayah pemiliknya. Dari konsep di atas, tampak bahwa lex rei sitae merupakan hukum atau aturan yang berlaku di suatu tempat di mana benda atau barang yang disengketakan berada. Dalam kasus tanah sebagai barang tidak bergerak (inmovable), aturan hukum tempat tanah berada seharusnya menjadi pedoman untuk mengatur semua transaksi yang berkaitan dengan tanah tersebut. Ketika tanah itu berada di wilayah Vo r s t e n l a n d e n , b a i k m i l i k r a j a ( vor stdo mein ) atau milik rakyat ( volksdomein ), aturan hukum yang berlaku seharusnya adalah hukum rajaraja Jawa. Pembatalan Sewa Tanah Di Vorstenlanden Tahun 1823: Kasus Kontra Lex Rei Sitae PERUBAHAN HUKUM ADAT Setelah pengambilalihan koloni Hindia Timur pada tanggal 16 Agustus 1816 dari Letnan Gubernur Jenderal Inggris John Fendall kepada Komisaris Jenderal Belanda, kekuasaan Belanda kembali ditegakkan di wilayah Nusantara. Semua yang dikuasai Inggris pada bulan September 1811, sesuai dengan isi Kapitulasi Tuntang, dikembalikan kepada Belanda. Oleh karena itu, kekuasaan Belanda diberlakukan juga di Jawa, sementara hubungan dengan raja-raja Jawa tetap dipertahankan seperti ketika berada di bawah kekuasaan Inggris (Brascamp, 1921: 1022; Fillet, 1895: 267270). Bertolak dari kondisi tersebut, daerah-daerah yang dianeksasi di bawah pemerintahan Raffles dari raja-raja Yogya dan Solo praktis menjadi hak dan kewenangan pemerintah Hindia Belanda. Begitu juga dengan jabatan residen yang mewakili pemerintah Inggris di kedua kuthagara digantikan oleh para pejabat Belanda (ANRI, 1808). Mereka memiliki status yang sama yaitu sebagai wakil pemerintah di Batavia dengan tugas utama untuk mengawasi pelaksanaan kontrakkontrak politik yang dibuat sebelumnya, memberikan nasehat kepada raja-raja Jawa, dan mewakili kepentingan pemerintah Eropa di Vorstenlanden. Salah satu residen ini adalah Nahuys van Burgst, seorang perwira angkatan darat yang telah mengabdi di Hindia Timur di bawah Marsekal Daendels dan berpengalaman di Vorstenlanden. Sosok ini lebih menunjukkan sebagai politikus daripada perwira militer, dan sekaligus seorang ekonom (Walderen-Rengers, 1947: 175). Nahuys menyadari bahwa Hindia Timur tidak banyak mengalami perubahan di bawah pemerintahan Inggris, khususnya Vorstenlanden. Jadi, pemerintahannya atas wilayah ini tidak membawa masalah. Namun demikian, justru persoalan terletak pada beban negaranya yang mengalami defisit anggaran sebagai akibat dari hilangnya koloni selama enam tahun, sementara ne g ar an ya s eda n g dala m p ros es pemulihan akibat peperangan di Eropa (Lauts, 1866: 102). Untuk itu, sebagai seorang pejabat, Nahuys wajib memikirkan bagaimana cara mengatasi krisis ekonomi dan anggaran yang melanda pemerintahnya. Selain itu, Nahuys juga memiliki koneksi yang luas di kalangan para pengusaha swasta di Belanda, yang terpaksa menganggur karena investasinya harus ditarik sebagai akibat perang. Ketika menerima jabatan sebagai residen di Yogyakarta, Nahuys telah mendengar sejumlah keluhan dari rekan-rekan pengusahany a mengenai p eluang melakukan investasi di tanah koloni (den Doel, 1996: 42). Mengingat sistem yang diterapkan oleh Komisaris Jenderal, yang didominasi oleh G.A.G.P. Baron van der Capellen, lebih menyukai dominasi dan eksploitasi oleh negara di sektor ekonomi daripada menyerahkan lahan itu kepada swasta dan pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator, para pengusaha swasta ini hampir tidak mendapatkan tempat untuk melakukan investasi di tanah-tanah pemerintah ( gouvernementlanden ). Kecuali tanah-tanah partikelir yang telah ada sejak era Daendels dan Raffles, praktis tidak ada usaha investasi modal swasta di sektor agraris (onderneming) yang bisa dibuka di wilayah pemerintah. Karena tekanan ini, para pengusaha tersebut kemudian mendekati Nahuys untuk mencari jalan keluar. Mengingat Nahuys tidak memiliki hubungan dekat dengan para Komisaris Jenderal, ia menemukan solusi untuk menampung tuntutan para investor swasta. Di mata Nahuys solusi ini harus bisa memberikan penyelesaian bagi sejumlah persoalan. Pertama, investasi swasta juga harus menguntungkan bagi keuangan negara lewat setoran pajak atau penyisihan hasil keuntungan penjualan produknya, menguntungkan investor sendiri, sekalig us memp er kaya keuangan pribadinya sebagai seorang pejabat pemerintah kolonial (Burgst, 1850: 116; Burgst, 1835: 346). Ketiga solusi itu kemudian dijumpai 118 : Jurnal Ilmu Humaniora, Vol. 14, No.2 Juli - Desember 2013: 100 - 219 oleh Nahuys dalam pembukaan lahan bagi investasi agraria swasta di Vorstenlanden, khususnya di Yogyakarta tempat ia b er k ua s a. D e ng a n m en gg un a ka n posisinya sebagai seorang pejabat Eropa tertinggi di Kesultanan Yogyakarta, Nahuys menjamin bahwa dirinya bisa memengaruhi elite penguasa pribumi di sana untuk menyewakan tanah-tanahnya kepada para pengusaha swasta bagi investasi perkebunan, dengan produk tanaman tropis sebagai komoditi utamanya. Kondisi ini dipermudah dengan situasi politik di Kesultanan Yogyakarta, yang disebabkan oleh kevakuman kekuasaan akibat pemerintahan perwalian (Soekanto, 1984: 20). Akan tetapi, suatu kendala besar dihadapi oleh Nahuys. Meskipun secara politik ia berada dalam posisi dominan untuk melakukan pemaksaan bagi penerimaan investasi di kalangan para pemegang apanage di Kesultanan Yogyakarta, hukum yang mengatur proses transaksi itu harus ada. Para investor Eropa juga menuntut adanya jaminan hukum dan kepastian kerja ketika menyerahkan modalnya untuk menyewa tanah serta untuk mengelola produktivitas kebunnya dari resiko pelanggaran atau pembatalan sepihak oleh para pemilik tanah. Mengingat dalam hukum adat Jawa yang selama ini digunakan untuk mengatur masalah agraria di Yogyakarta, yaitu Hangger Sadasa, tidak memuat trans aks i s ewa- menyewa kecual i peminjaman tanah, jaminan hukum itu tidak bisa diperoleh. Situasi ini jelas menimbulkan ragu-ragu di kalangan para investor, yang berarti ancaman gagal terhadap rencana Nahuys (Nes, 1850: 207).2) Untuk mengatasi hal tersebut, Nahuys kembali menggunakan kepandaiannya sebagai seorang politikus. Pada masa itu, tahun 1817-1818, Sultan 3) Hamengku Buwono IV belum memerintah sendiri dan pemerintahan dipegang oleh para wali. Salah satu wali yang dominan adalah K.G.P.A. Paku Alam I, yang pernah berhutang budi karena diselamatkan oleh Nahuys di Cirebon saat akan dihukum mati oleh Daendels pada tahun 1810. Melalui wali ini, dan dengan dukungan Patih R.A. Danurejo IV, Nahuys kemudian merancang upaya untuk mengubah ketentuan dalam Hangger Sadasa (Anon, 1844: 49). Perubahan terjadi pada tanggal 4 Oktober 1818 dengan adanya beberapa pasal yang memungkinkan transaksi sewa-menyewa tanah dari para bangsawan Jawa, khususnya pemegang apanage yang dianggap subur, kepada investor swasta. Di antaranya adalah pasal 20 sebagai berikut (Anon, 1868, 1-16): Over het verhuren en verpanden van desas Ook bij het verhuren en verpanden van desas, zal men een behoorlijke overeenkomst aangaan. Wanneer daaruit geschillen onstaan zullen dezelve even als in het voorgaande artikel afgedaan worden. Tentang persewaan dan penggadaian desa Juga dalam persewaan dan penggadaian desa-desa, orang hendaknya membuat suatu kesepakatan yang sewajarnya. Ketika dari situ sengketa muncul, hal itu akan diselesaikan seperti pada pasal sebelumnya. Selanjutnya juga pasal 21, Over het verpachten, verhuren of verpanden van landen Zonder schriftelijke overeenkomst Wanneer desas zonder schriftelijke overeenkomst verpacht, verhuurd of verpand worden en daarover geschillen ontstaan, zullen dezelve zoo veel doenlijk beslist worden, maar dan verbeuren beide partijen Hal ini disebabkan karena dalam konsep Jawa terdapat pengertian adol sende, dari kata disendekake atau disandarkan. Jadi maksudnya di sini adalah menitipkan atau mungkin dalam pengertian modern menggadaikan dan menjaminkan. Namun pengertian sewa tidak pernah ada pada orang Jawa tampak dari istilah adol yang lebih menekankan menjual. 119 Pembatalan Sewa Tanah Di Vorstenlanden Tahun 1823: Kasus Kontra Lex Rei Sitae eene boete door de overheat te evenredigen. Tentang pemborongan, penyewaan atau penjaminan tanah-tanah tanpa kesepakatan tertulis Ketika desa-desa tanpa kesepakatan tertulis diborongkan, disewakan atau dijaminkan dan sengketa tentang hal itu terjadi, begitu banyak yang perlu diputuskan, tetapi kedua pihak harus menanggung denda sama seperti yang diputuskan oleh penguasa. Dari kedua pasal tersebut di atas, jelas bahwa peluang bagi persewaan tanah terbuka lebar dari pihak para penguasa pribumi. Hal ini telah dijamin oleh Nahuys dan disampaikan kepada para calon investor (ANRI, 1818).3) Untuk memperkuat posisi para investor ini, Nahuys kemudian melaporkan semua hasil kerjanya kepada pemerintah di Batavia dan mendesak Komisaris Jenderal agar memberikan izin sekaligus jaminan bagi investasi modal swasta di Vorstenlanden. Atas tanggungan Nahuys bahwa kehadiran mereka tidak akan membahayakan dan justru akan meningkatkan produksi tropis yang tidak mampu dilakukan sendiri oleh pemerintah kolonial, pada tanggal 22 Desember 1818 Komisaris Jenderal menerbitkan Resolusi yang mengijinkan para pemilik modal swasta melakukan transaksi persewaan tanah dan investasi di sektor perkebunan.4 ) Dengan diterbitkannya Resolusi itu, pada awal tahun 1819 sejumlah investor swasta masuk ke wilayah Kesultanan Yogyakarta dan melakukan transaksi, atas perantaraan Nahuys dan Patih Danurejo IV,5) dengan sejumlah bangsawan pemilik 3) tanah apanage . Mereka melakukan persewaan selama jangka waktu antara 1015 tahun dengan dibayar di muka, setidaknya uang muka separuh dan sebulan kemudian dilunasi. Dengan proses ini, tanah-tanah apanage yang sebelumnya merupakan lahan pertanian padi dan tanaman pangan untuk memasok kebutuhan para patuh berubah menjadi lahan perkebunan tanaman tropis terutama kopi (Anon, 1909: 227). Di samping kesuburan tanah yang menjadi pesona tersendiri sebagai daya tarik bagi para pemilik modal, Nahuys mempromosikan pesona lain pada tanahtanah apanage ini. Pesona ini adalah sistem yang berlaku, yaitu hubungan patron-klien dengan ikatan feodal sebagai fondasinya. Di bawah kekuasaan para patuh, petani atau cacah yang menghuni dan ikut menikmati hasil tanah-tanah apanage wajib bukan hanya menyetorkan hasilnya tetapi juga tenaganya untuk kepentingan tertentu dari para patuh (ANRI, 1825; Haspel, 1985: 14). Dengan persewaan tanah, persembahan ganda dialihkan dari patuh kepada pengusaha swasta, sesuatu yang mirip dengan sistem Preanger Stelsel oleh pemerintah di wilayah Priangan. Ketika wilayah Kesultanan Yogyakarta telah dipenuhi oleh petakpetak tanah sewaan, sejumlah investor lain yang tidak mendapatkan kesempatan berinvestasi di Yogyakarta mendesak Nahuys untuk mencari peluang lain. Kini pandangan Nahuys diarahkan ke Surakarta. Akan tetapi, kondisi di Surakarta berbeda, mengingat Sunan Paku Buwono IV masih bertahta. Selain ia m em er i nt ah l a ng s ung d an t i da k Pada hari pengundangan Hangger Sadasa, Nahuys juga memprakarsai kesepakatan antara dua patih dari Yogya dan Solo agar memberikan jaminan bersama bagi keselamatan dan kelancaran usaha para investor di wilayah mereka. Sebagai dasar dari keputusan ini adalah Staatsblad van Nederlandsch Indië over het jaar 1818 no. 67, yang memberikan kepastian hukum bagi orang-orang Eropa untuk menanamkan modalnya dalam pengembangan sektor perkebunan dan pertanian. Sesuai dengan kesepakatan tanggal 4 Oktober 1818, peran Danurejo IV dalam hal ini sangat besar. Bahkan Nahuys sendiri tidak mau membubuhkan persetujuannya apabila tidak terdapat cap dari patih Yogyakarta ini dalam kontrak sewa tanah antara investor asing dan pemegang apanage. Periksa Van der Kemp (1890: 150). 120 : Jurnal Ilmu Humaniora, Vol. 14, No.2 Juli - Desember 2013: 100 - 219 menggunakan perwalian, raja ini juga dikenal sebagai anti-Eropa. Oleh karena itu, Nahuys tidak mau berspekulasi untuk membujuk Sunan PB IV bersedia menerima investasi modal swasta Eropa di wilayah kekuasaannya. Lebih-lebih pada akhir tahun 1819 Sunan PB IV baru saja berkonflik dengan Residen Solo Prehn yang berakhir dengan pemindahan Prehn dari jabatannya (ANRI, 1816). Meskipun peristiwa itu dianggap sebagai kemenangan Sunan, justru kepergian Prehn memberi peluang bagi Nahuys untuk bisa mendekati Sunan PB IV. Hal ini dimungkinkan oleh hubungan dekat Nahuys dengan panglima militer Belanda di Jawa, Mayor Jenderal H.M. De Kock yang berpengaruh pada Gubernur Jenderal Baron van der Capellen. Oleh karena itu kekosongan jabatan residen di Solo segera dirangkap oleh Nahuys van Burgst. Meskipun pada mulanya Nahuys tidak banyak berbuat mengingat sikap hati-hatinya terhadap Sunan dan kesibukannya di Yogyakarta, kematian Sunan PB IV dan penggantiannya dengan Sunan PB V yang masih muda memberi kesempatan Nahuys untuk bertindak seperti di Yogyakarta (ANRI, 1820). Langkah pertama adalah mendekati wali Sunan, Pangeran Adipati Aryo Buminoto, untuk merevisi Hangger Sadasa seperti yang dilakukan di Yogyakarta. Langkah ini berhasil dilakukan sehingga pada akhir tahun 1820 Kesunanan Surakarta juga terbuka bagi investasi modal swasta. Akan tetapi, para bangsawan Surakarta, terutama Buminoto dan Patih Sosrodiningrat II, lebih berhatihati daripada bangsawan di Yogyakarta (ANRI, 1821). Mereka tidak menyewakan tanah apanagenya dalam jangka waktu lama melainkan tiap tahun yang terus diperpanjang. Meskipun lahan yang disewa lebih banyak daripada di Yogyakarta, persewaan di Surakarta cenderung terletak terpisah-pisah dan tidak terkonsentrasi. Kedua faktor ini, persewaan tahunan dan lokasi perkebunan, membedakan karakter dengan persewaan di Yogyakarta dan kelak akan berpengaruh pada krisis politik 121 di Kesultanan Yogyakarta tahun 1825. PEMBATALAN SEWA TANAH Perkembangan persewaan tanah di Vorstenlanden berlangsung dengan lancar. Para investor, khususnya di Yogyakarta, be rh as i l m en d ap at ka n a pa y an g dibutuhkan dan melakukan penanaman produk tropis. Mereka pada umumnya m en an am t a n a m a n t r o p i s u n tu k kepentingan pasaran dunia yang memberikan prospek keuntungan jauh lebih besar daripada tanaman domestik. Produk kopi merupakan prioritas bagi lahan yang sesuai untuk tumbuhnya tanaman ini, karena kopi menjadi produk dengan posisi penawaran tertinggi dibandingkan yang lain. Di Yogyakarta, yang persewaannya berlangsung selama 10-15 tahun, periode bagi produktivitas tanaman kopi menjadi jauh lebih memungkinkan daripada di Surakarta yang periodenya berlangsung lebih singkat. Di samping itu, penanaman yang berlangsung lebih dahulu di Yogyakarta memungkinkan produksi lebih awal diperoleh daripada di Surakarta. Karena lokasinya di wilayah ya n g d i l ua r k e ku a s a an h uk um pemerintah, para pengusaha ini memiliki kemampuan untuk langsung mengekspor hasil perkebunannya ke pelabuhanpelabuhan di Batavia dan Semarang. Hasil panen pertama yang dijual pada akhir tahun 1822 telah membuat pangs a pasar kopi internasional, khususnya pemasaran bagi kopi tropis Hindia, mengalami lonjakan. Harga kopi internasional yang cukup tinggi telah berhasil memberikan keuntungan bagi produsen kopi, termasuk para pengusaha penyewa tanah di Vorstenlanden . Sementara para penyewa tanah di Solo masih belum sempat memanen produknya, para penyewa tanah di Yogyakarta telah menikmati keuntungan sehingga beberapa ada yang berpikir untuk memperpanjang masa sewa mereka. Begitu juga dengan para pemilik tanah apanage yang menerima uang sewa tunai segera bisa menikmati hasil dari penguasaan tanahnya. Pembatalan Sewa Tanah Di Vorstenlanden Tahun 1823: Kasus Kontra Lex Rei Sitae Akan tetapi, justru kondisi ini menimbulkan dampak negatif pada pihak yang tidak terlibat dalam persewaan itu, yaitu pemerintah kolonial. Melimpahnya produksi kopi dari Vorstenlanden dan pemasarannya bersama dengan kopi pemerintah telah membuat harga kopi di pasaran dunia menurun mengingat jumlah pasokan kemudian menjadi lebih banyak daripada permintaan. Penurunan harga ini membawa dampak pada perolehan anggaran negara dari sektor perkebunan terutama kopi, karena pemerintah masih mengandalkan pada sistem lama yaitu verplichte leverantie dan pembelian produk wajib. Sementara itu, biaya produksi oleh para pengusaha swasta di Vorstenlanden bisa ditekan dengan memanfaatkan sistem ikatan primordial yang berlaku di tanah-tanah sewaan apanage. Meskipun tidak menderita kerugian, jumlah penerimaan yang tidak sesuai dengan target memengaruhi defisit anggaran belanja negara. Untuk itu, pada awal tahun 1822 Gubernur Jenderal van der Capellen memerintahkan Direktur Keuangan H.J. van der Graaff untuk melakukan penyelidikan terhadap hal ini (ANRI, 1823). Hasil penyelidikan van der Graaff yang laporannya diajukan pada tanggal 23 Maret 1822 menunjukkan bahwa penyebab berkurangnya pemasukan adalah turunnya harga kopi di pasaran dunia, akibat pasokan dan kompetisi kopi dari Vorstenlanden terhadap produksi kopi pemerintah (ANRI, 1822). Atas usul Van der Graaff, Baron van der Capellen kemudian m em pe r t i mb an gk an p en g a mb il a n tindakan yang tepat. Risiko teguran dari Raja Willem II yang memercayakan produktivitas koloni Hindia Belanda 6) kepadanya membuat van der Capellen memutuskan untuk mengakhiri kondisi ini. Oleh karena itu, dengan memanf aatkan pos isinya sebagai penguasa tertinggi tanah koloni dan wakil Raja Belanda di Hindia Belanda, van der Capellen melarang orang-orang Belanda melakukan persewaan tanah di Vorstenlanden pada bulan Mei 1823. Banyak pihak yang menunjukkan reaksi terhadap keputusan ini. Pertamatama tentu saja adalah mereka yang terlibat langsung dalam persewaan tanah, yaitu para penyewa tanah. Mereka merasa bahwa modal mereka telah terlanjur diinvestasikan pada sektor agraris dan produksi yang mereka peroleh belum mampu mengembalikan jumlah modalnya. Oleh karena itu, kembali melalui Nahuys, mereka menuntut agar Baron van der Capellen mencabut keputusan tersebut. Nahuys pada mulanya mendesak van der Capellen untuk melakukannya, tetapi setelah usaha itu gagal Nahuys akhirnya meminta pengunduran diri sebagai Residen Yogyakarta dan Surakarta. Bahkan, kemudian ia tidak lagi mau tinggal di Hindia Timur dan kembali ke Negeri Belanda.6) Dengan ditinggalkan oleh patronnya, para penyewa tanah kemudian mengajukan gugatan mereka langsung kepada Raja Willem II. Raja Willem II yang mendengar tuntutan ini kemudian menyerahkan kepada Baron van der Capellen untuk menyelesaikannya. Atas saran van der Graaff, Van der Capellen memaksa raja-raja Yogyakarta dan Surakarta agar para pemilik tanah apanage mengembalikan uang sewa yang tersisa kepada para penyewa tanah untuk mencegah terjadinya kerugian dalam usaha (Spengler, 1863: 29-30). Nahuys sendiri menyatakan bahwa apa yang dituduhkan oleh van der Graaff tidak benar termasuk kecurigaan kolonisasi. Persewaan tanah di Vorstenlanden yang disponsori olehnya hanya merupakan aktivitas modal swasta, yang akan dimanfaatkan bagi kepentingan pemerintah dan penduduk pribumi bila diarahkan sesuai dengan tujuan negara. Dengan pemberdayaannya, modal swasta bisa menjadi kekuatan ekonomi utama yang memperkuat fondasi keuangan koloni Hindia Belanda (Burgst, 1847: 13). 122 : Jurnal Ilmu Humaniora, Vol. 14, No.2 Juli - Desember 2013: 100 - 219 Bagi para pemilik tanah di Surakarta, perintah ini tidak begitu bermasalah karena persewaan yang berlangsung hanya dibayar setiap tahun. Akibatnya, jumlah uang yang diserahkan kembali kepada para penyewa tanah tidak ter lalu bes ar (Nes, 1 84 4: 134). Sebaliknya, bagi para pemilik tanah di Yogyakarta, hal ini mengakibatkan terjadinya krisis di antara para pemilik apanage. Mereka telah menggunakan uang sewa yang ada dan tidak lagi mampu mengembalikan tuntutan itu. Mengingat tekanan dari pemerintah kolonial yang begitu keras dan perintah raja untuk mengembalikannya, banyak dari pemilik tanah ini yang terjebak hutang, baik kepada keraton maupun kepada kreditur swasta, dengan bunga tinggi. Bagi mereka yang berhutang kepada keraton, mereka harus rela bahwa tanah apanagenya diambil alih keraton dan jika memungkinkan, mereka menerima jumlah lahan yang jauh lebih kecil (dikenal sebagai tanah pancasan). PENUTUP Fenomena persewaan tanah di Vorstenlanden menunjukkan suatu kasus yang menarik untuk dicermati. Dari aspek politik, jelas jawaban bisa ditemukan sebagai bentuk dominasi kekuasaan kolonial pada penguasa pribumi Jawa, meskipun dalam hal ini bentuk kekuatan kolonial masih harus dibedakan antara pemerintah Belanda dan kekuatan modal swasta yang ironisnya saling berhadapan. Dengan demikian tidak mungkin menggambarkan suatu kondisi polarisasi antara kekuatan kolonial dan kekuatan pribumi dalam konteks ini. Akan tetapi, dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum, simpulan tersebut bisa dipertegas atau bahkan sedikit berbeda. Pendekatan hukum akan mengungkap bagaimana legalitas dari tindakan atau kebijakan yang dijalankan ol eh s al ah s atu p ih ak s eh in gg a menimbulkan persoalan hukum yang harus dicari solusinya berdasarkan nilainilai yuridis yang berlaku. Seperti telah diungkapkan, dalam 123 peristiwa ini ada tiga pihak yang berkepentingan : pemerintah kolonial, penyewa tanah dan pemilik tanah. Dalam transaksi sewa-menyewa tanah hanya dua pihak yang berkepentingan langsung. Meskipun Residen Nahuys memberikan kesaksian, sifatnya adalah hanya mengetahui tanpa ada hak pengesahan apa pun. Justru pengesahan yang berlaku adalah cap keraton, yang dalam hal ini dipegang oleh Patih Danurejo IV. Hal ini membuktikan bahwa kewenangan hukum tertinggi dipegang oleh keraton, bukan oleh pemerintah Batavia. Bukti lain bahwa pemerintah di Batavia tidak berwenang atas transaksi ini adalah dalam persewaan tanah pemerintah tidak memungut apapun, baik atas transaksinya maupun produk yang d i h a s i l k an n y a . K e t i d a k m a mp u a n pemerintah kolonial untuk memungut pajak, kecuali di pelabuhan ketika produk itu diekspor, menegaskan tidak adanya kewenangan pemerintah terhadap transaksi persewaan tersebut. Tentu saja kondisi ini menjadi sangat berbeda dengan keputusan pemerintah untuk membatalkan persewaan tersebut. F ak t or ke d ua l ain nya ya ng membuktikan kelemahan keputusan pemerintah adalah penerapan prinsip lex rei sitae, yaitu pemberlakuan hukum di tempat transaksi berlangsung. Dalam proses sewa-menyewa tanah tersebut, hukum raja-raja Jawa yang dimuat dalam Hangger Sadasa dinyatakan sebagai aturan yang diberlaku kan unt uk mengaturnya. Hal ini dipertegas dengan pengesahannya oleh pihak Keraton Yogyakarta lewat cap yang dipegang patih. Dengan demikian, ketika van der Capellen mengeluarkan keputusan, meskipun dimuat dalam Staatsblad, ia melakukan pelanggaran prinsip lex rei sitae karena Staatsblad merupakan bentuk perundangan yang berlaku di tanah pemerintah, bukan di tanah raja-raja (Vorstenlanden). Dengan melihat dua pandangan tersebut di atas, dalam hal ini bisa dikatakan bahwa keputusan van der Capellen untuk membatalkan persewaan Pembatalan Sewa Tanah Di Vorstenlanden Tahun 1823: Kasus Kontra Lex Rei Sitae t an ah , m e s k i p u n d e n g a n a l as a n keterkaitannya pada individu penyewa tanah, tetap dinyatakan tidak sah. Individu sebagai kawula pemerintah hanya berhak mendapatkan perlindungan, dan bukan pada intervensi dalam urusan bisnisnya. Dengan demikian kesimpulan dalam hal ini bisa ditarik bahwa pemerintah kolonial melakukan pelanggaran hukum terhadap kewenangan raja-raja Jawa, dengan risiko terjadinya Perang Diponegoro sebagai bentuk hukumannya. DAFTAR PUSTAKA Adams , L. 1931. “Geschiedkundige aanteekeningen omrent de Residentie Madioen.” Djawa, Jilid XIX. Anon. 1844. ”Overzicht van de voornaamste gebeurtenissen in het Djocjakartasche rijk sedert deszelf stichting (1755) tot aan de einde van het Engelsche Tusschenbestuur ( 181 5 ). Tijdch ri ft vo or Nederlandsch Indië, Jilid IV Anon. 1868. Korte Inhoud der Javaansche wetboeken en beschrijving der Javaansche gebruiken en instellingen. Soerakarta: Jaspers & Co. Anon. 1909. ”Mr. C.T. als Minister van Koloniën, in zijne veroordeeling van het beleid der regeering van den G ou ve r n eu r Bar on v an d er Capellen.” BKI, Jilid 62 ANRI. 1773. Punika serat pemut menggah bumi pasiten Kanjeng Sultan kadamel ing Semawis tahun 1773, bundel Yogyakarta no. 258. ANRI. 1808. Ontwerp van een vast ceremonieel van residenten aan de hooven van Soerakarta en Djocjakarta over het jaar 1808, bundel Solo nomor 55/9. ANRI. 1818. Contract tusschen den rijksbestuurder van Soerakarta en Djokjakarta, Sosrodiningrat en Danoeredjo, 4 Oktober 1818, bundel Solo nomor 371. ANRI. 1819. Surat Komisaris Jenderal Baron van der Capellen kepada Residen R. Prehn tanggal 30 November 1819 nomor 73, bundel Solo nomor 108. ANRI. 1820. Extract uit het register der handelingen en besluiten van den secretaries van staat Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië, 24 Maart 1820 no. 23, bundel Solo nomor 109. ANRI. 1821. Piagemboek aangelegd op order van de waard. Residen Nahuys 1821, bundel Solo, nomor 481. ANRI. 1822. Verhuurde gronden in de Javasche Vorstenlanden over het jaar 1822, Bundel Solo nomor 482. ANRI. 1823. Surat Sekretaris Umum Bousquet kepada Gubernur Jenderal van der Capellen tanggal 14 Januari 1823, bundel Solo nomor 482. ANRI.1825. Landverhuuring in Vorstenlanden 1825, bundel Yogya nomor 471 Brascamp, A.J.B. 1921. ”De contracten van 1811 en 1812 met Soerakarta en Djocjakarta.” Tectona, Jilid XIV Burgst, G.B. Nahuys van. 1835. Verzameling van Officiële rapporten betreffende den oorlog op Java in de jaren 1825-1830, eerste deel. Deventer: M. Ballot. Burgst, Baron Nahuys van. 1847. Beschouwingen over Nederlandsch Indië. ’s Gravenhage: Gebroeders Belifante. Burgst , Baron Nahuys van. 1850. ”Partikulier Landbezit op Java.” Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 124 : Jurnal Ilmu Humaniora, Vol. 14, No.2 Juli - Desember 2013: 100 - 219 Jilid 1. Doel, H.W. van den. 1996. Het Rijk van Insulinde: opkomst en ondergang van een Nederlandse kolonie. Amsterdam: Prohemeus. Fillet, P.W. 1895. De Verhouding der Vorsten op Java tot de Ned. Indische Regeering. ’s Gravenhage: Martinus Nijhoff Haspel, C.Cb. van den. 1985. Overwigt in Overleg: Her vormingen van Justitie, grondgebruik en bestuur in de Vorstenlanden op Java 18801930. Dordrecht: Foris Publ. Kemp, Ph. Van der. 1890. ”Het rapport van den hoofdinspecteur van financieën H.J. van der Graaff; dat aanleiding is geweest tot de intrekking der landverhuur in de Vorstenlanden.” Tijdschrift van Nijverheid en Landbouw in Nederlandsch Indië, Jilid XLI. Kemp, Ph. van der. 1897. De Economische Oorzaken van de Java Oorlog van 1825-1830. ’s Gravenhage : M. Nijhoff Lauts, G. 1866. Geschiedenis van de vestiging, uitbreiding, bloei en verval van de magt der Nederlanders in Indië, zesde deel. Amsterdam: Frederik Muller. 125 Nes, J.F.W. van, “Landverhuur in de Vorstenlanden” dalam Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, tahun 1850, jilid 2. N e s , Wa l v a r e n v a n . 1 8 4 4 . ” Ve r h a n d e l i n g e n o v e r d e waarschijnlijke oorzaken, die de aanleiding tot de onlusten van 1825 en de volgende jaren en de vorstenlanden gegeven hebben.” Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, Jilid IV. Sarcevic, Peter, and Paul Volken. 2007. Yearbook of Private International Law, Vol. III. Berlin: Kluwer Publ. Soekanto. 1984. Hubungan Diponegoro dan Sentot. Jakarta: Bina Aksara Spengler, Johan Albert.1863. De Nederlandsche Oost Indische Bezittingen onder het bestuur van den Gouverneur Generaal G.A.G.P. Baron van der Capellen, 1819-1826. Utrecht: Kemink en Zoon. Staatsblad van Nederlandsch Indië over het jaar 1818 no. 67 Walderen-Rengers, Daniel Wilco van. 1947. The failure of a Liberal Colonial Policy, Netherlands East Indies, 1816-1830. The Hague: Martinus Nijhoff.