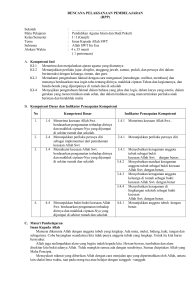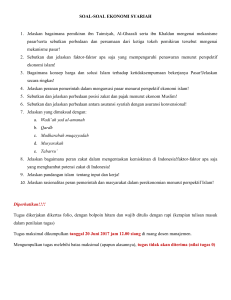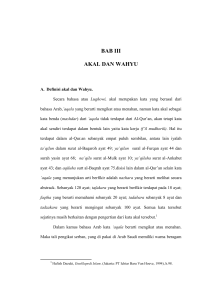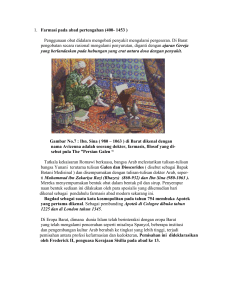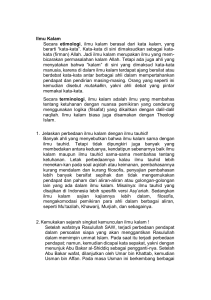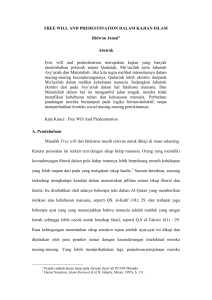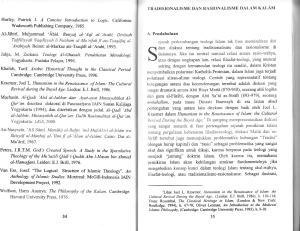DISKUSI UTAN KAYU Wahhabisme - Center for Islamic Pluralism
advertisement
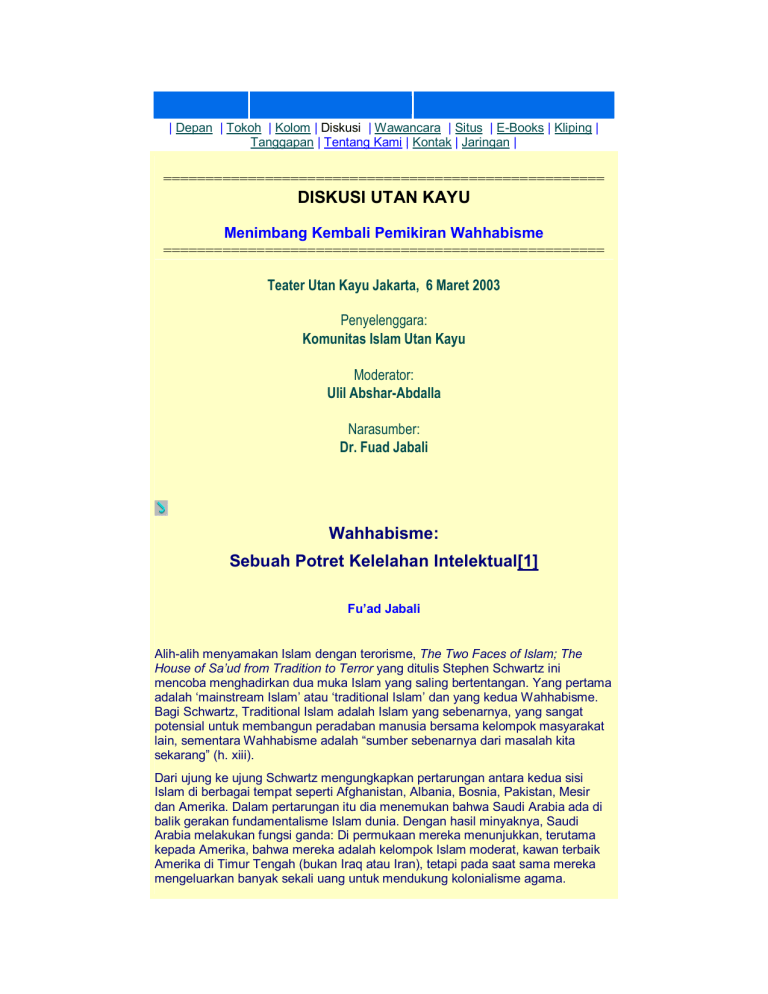
| Depan | Tokoh | Kolom | Diskusi | Wawancara | Situs | E-Books | Kliping | Tanggapan | Tentang Kami | Kontak | Jaringan | ==================================================== DISKUSI UTAN KAYU Menimbang Kembali Pemikiran Wahhabisme ==================================================== Teater Utan Kayu Jakarta, 6 Maret 2003 Penyelenggara: Komunitas Islam Utan Kayu Moderator: Ulil Abshar-Abdalla Narasumber: Dr. Fuad Jabali Wahhabisme: Sebuah Potret Kelelahan Intelektual[1] Fu’ad Jabali Alih-alih menyamakan Islam dengan terorisme, The Two Faces of Islam; The House of Sa’ud from Tradition to Terror yang ditulis Stephen Schwartz ini mencoba menghadirkan dua muka Islam yang saling bertentangan. Yang pertama adalah ‘mainstream Islam’ atau ‘traditional Islam’ dan yang kedua Wahhabisme. Bagi Schwartz, Traditional Islam adalah Islam yang sebenarnya, yang sangat potensial untuk membangun peradaban manusia bersama kelompok masyarakat lain, sementara Wahhabisme adalah “sumber sebenarnya dari masalah kita sekarang” (h. xiii). Dari ujung ke ujung Schwartz mengungkapkan pertarungan antara kedua sisi Islam di berbagai tempat seperti Afghanistan, Albania, Bosnia, Pakistan, Mesir dan Amerika. Dalam pertarungan itu dia menemukan bahwa Saudi Arabia ada di balik gerakan fundamentalisme Islam dunia. Dengan hasil minyaknya, Saudi Arabia melakukan fungsi ganda: Di permukaan mereka menunjukkan, terutama kepada Amerika, bahwa mereka adalah kelompok Islam moderat, kawan terbaik Amerika di Timur Tengah (bukan Iraq atau Iran), tetapi pada saat sama mereka mengeluarkan banyak sekali uang untuk mendukung kolonialisme agama. Islam Tradisional Islam Fundamentalis/Wahhabisme Moderation, equanimity, patience and fairness (h. 8), love and admiration of his [the prophet’s] quest for compassionate (h. 9), compassion and mercy (h. 22), just and tolerant (h. 29), consensus (h. 43), pluralist and lovers (h. 45), tolerant, pluralist and spiritual (h. 63), based its guidance on knowledge and ethics (h. 132) separatism, supremacism, frenzy, aggression (h. 8), ignore the personality of the Prophet (h. 9), purism and extrimism (h. 22), separatism, purism, and fundamentalism (h. 35) hunters of heresy and haters (h. 45), [based its guidance on] violence and subversion (h. 132) belief alone is sufficient for salvation (h. 43) Faith must be judged in terms of outward conduct (h. 43) Mystics (h. 45) legalists (45) Abrahamic solidarity, Abrahamic dialog, Abrahamic reconciliation (h. xx-xxi) Shi’ah (h. 37) Khawarij (h. 35) Ikhwan (h. 92), “who reproduced the mentality of the Khawarij (105) Ikhwanul Muslimin (h. 129) Ali b. Abi Talib (h. 36) Ibn Hanbal (h. 41) Abu Hanifa (h. 41) Ibn Hazm (h. 47) Al-Hallaj (h. 46) Ibn Taymiyya (h. 54) Jalaluddin Rumi (h. 46) Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhab (h. 66) Al-Ghazali (h. 46) Mawdudi (h. 131) Ibn al-‘Arabi (h. 47) Usama b. Laden Ibn Rushd (h. 47) Nasser (h. 129) Islam di Spanyol (abad 8-15), Turki Uthmani (abad 15-18), Balkan (abad 20) (Albania, Sarajevo, Bosnia, dll) Saudi Arabia abandonment of four traditions [Maliki, Hanafi, Hanbali and Shafi’i)] although his followers would claim to be the followers of the Hanbali school (h. 71) Crisis, social dislocations – wars, migrations, economic adjustments (h. 67) totalitarian system – a dictatorship resting on an idiological militia (h. 104) Muslim Public Affairs Muslim (MPAC), Council on American-Islamic Relations (CAIR), American Muslim Council (AMC), American Muslim Alliance (AMA) Islamic Society of North America (ICNA), Muslim Students Association (MSA) Schwartz menyebut Hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah sebagai peristiwa penting dalam pemunculan dua muka Islam yang berbeda tersebut. Dia bisa dilihat secara bertentangan: pertama sebagai sikap pemisahan diri dari msyarakat non Muslim, yang kemudian akan membawa pada purisme dan ekstrimisme; kedua sebagai awal memasuki dunia, walaupun dalam keadaan sulit, yang akan membawa pada pluralisme dan toleransi (h. 11). Di Madinah Mabi menggariskan prinsip bahwa konflik harus diselesaikan dengan cara damai, berbagi tanggung jawab, arbitrasi dan mediasi. Tradisional Islam adalah Islam yang berdasar pada kontrak, yang justeru menjadi dasar dari sebuah negara modern (h. 15). Schwartz menolak istilah ‘Islam politik’ sebagai lawan dari Islam keyakinan, karena semua Islam adalah politik (h. 15). Sementara itu, Khawarij, gerakan separatisme dan fundamentalisme pertama dalam Islam, melihat Hijrah dengan cara kedua, dan ini yang kemudian diadopsi oleh Wahhabisme (h. 97). Islam Khawarij adalah Islam yang menarik diri ke dalam, sementara Islam tradisional adalah Islam yang merangkul dan menyebar. Jika saja sikap mengkerut Khawarij ini yang dominan maka Islam tidak akan berhasil membangun peradaban seperti yang diperlihatkan sejarahnya. Sebagai seorang Yahudi, Schwartz sangat mengagumi masyarakat Muslim di Spanyol yang telah memberikan perlindungan yang baik terhadap kelompok agama lain, terutama Yahudi. Di Spanyollah tradisi intelektual dan spiritual Yahudi berkembang di bawah pengaruh Islam. “Islam telah membebaskan hati dan fikiran orang-orang yang dalam pencarian baik dari kalangan Yahudi maupun Kristen” (h. 53). Ketika Granada jatuh ke tangan Kristen pada tahun 1492, yang diikuti dengan inquisi, pola hubungan Islam, Yahudi dan Kristen berubah. Orang-orang Yahudi yang diusir dari Spanyol dan Portugis diterima dengan baik di wilayah Turki Uthmani. Melihat bagaimana mereka diperlakukan, Schwatz mempertanyakan bayangan buruk orang-orang Eropa (baik Yahudi maupun Kristen) terhadap konsep dhimmi (status non Muslim di wilayah kekuasaan Islam), misalnya. Perlakuan sultan-sultan Turki terhadap Yahudi jauh lebih baik disbanding perlakukan penguasa-penguasa Kristen, belum lagi kalau dibandingkan dengan Holocaust pada abad ke 20. Bagi Schwartz, sejauh hubungan antara Barat-Islam atau Yahudi-Kristen-Islam, masyarakat Muslim yang ada di Balkan bisa dijadikan model. Mereka orang Eropa yang Islam, atau orang Islam yang sudah di-Eropa-kan, dan karena itu, mereka tidak anti-Barat dan memiliki kadar penerimaan yang baik terhadap Yahudi dan Kristen. Islam mereka Islam tradisional (terutama sufisme) yang sekarang justeru sedang terancam karena ekspansi Wahhabisme (dengan dukungan finansial dari Saudi Arabia) pasca peperangan. Namun uniknya, dan ini menjadi kredit tersendiri bagi Schwartz, tidak seperti di tempat lain, mereka gigih melakukan resistensi terhadap ekspansi ini. Kebencian yang berlebihan, membuat Schwartz membuat penilaian yang tidak adil kepada Wahhabisme. Bani Umayyah dan Abbasiyyah, yang bisa dianggap sebagai pendukung Islam Tradisional, yang menjadi musuh orang Khawarij kelompok ekstrim pertama dalam sejarah Islam, juga melakukan kesalahan besar yang menyebabkan hilangnya banyak nyawa Misalnya perlakuan mereka pada Shi’ah. Bani Umayyah, yang kemudian menjadi penguasa Spanyol, yang dikagumi Schwartz, dibangun atas dasar penolakan pada Khalifah ‘Ali yang shah, sementara Abbasiyyah melakukan terror besar-besaran terhadap lawanlawannya, terutama turunan Umayyah, sebelum akhirnya membangun dinasti sendiri. Membaca buku ini, orang akan digiring untuk melihat Wahhabisme selalu identik dengan kejahatan dan dianggap berada di luar rumah Islam yang sebenarnya. Tulisan berikut ini akan mencoba memahami akar teologis dari gerakan ini, paling tidak untuk menegaskan kembali bahwa Wahhabisme merupakan salah satu hasil dari pergumulan masyarakat Islam yang panjang dalam memahami tauhid, dan semuanya berawal dari niat baik. Secara singkat akan didiskusikan beberapa persoalan teologis: sifat Tuhan, perbuatan manusia, sumber nilai, penciptaan alam, monisme dan pemujaan orang suci. Dari keenam masalah ini akan kelihatan bahwa munculnya berbagai gerakan dalam Islam antara lain berakar dari pertarungan mereka dalam memahami ajaran Islam yang paling dasar: tauhid. Kenapa Wahhabi sangat membenci praktek-praktek keagamaan sufi, pemikiran ktritis dan terbuka, dan sangat kaku juga bisa difahami lewat perdebatan teologis ini. Akar Teologis Wahhabisme Wahhabisme atau Wahhabiyyah bukanlah nama yang dipakai oleh para pengikut Muhammad b. ‘Abd al-Wahhab (w. 1787) untuk menyebut dirinya. Walaupun nama pendirinya Muhammad, lawan-lawannya tidak mau menyebut aliran ini Muhammadiyyah (seperti halnya mereka menyebut Malikiyyah, Hanafiyyah, Hanbaliyyah dan Syafi’iyyah). Nampaknya, Muhammadiyyah bukanlah nama yang cocok karena bisa diidentikkan dengan pengikut Nabi Muhammad, padahal, di mata pengkritiknya, justeru mereka mengingkari semangat Nabi. Walaupun kurang baik, Wahhab, salah satu nama Tuhan yang tepat, dijadikan nisbat gerakan yang sekarang banyak dikritik ini. Para pengikut Ibn ‘Abd al-Wahhab sendiri lebih senang menyebut dirinya Muwahhidun (orang-orang yang mengesakan Tuhan), sebab menurut mereka, gerakan mereka semata-mata untuk menegakkan kembali kemurnian Tauhid Islam yang sudah terkotori oleh kepercayaan dan tradisi lokal yang tidak ada dasarnya dalam al-Qur’an dan Hadith. Untuk memahami klaim mereka, kita akan melihat ke belakang, ke masa Ahmad ibn Hanbal (w. 855), tokoh yang sangat erat dikaitkan dengan gerakan radikal Islam. Ibn Hanbal hidup pada saat dunia Islam dibanjiri filsafat Hellenisme. Gerakan rasional, yang dimotori Mu’tazilah, dalam penafsiran Islam sangat kuat sehingga, paling tidak di mata kaum Tradisionalis, mengancam otoritas wahyu. Dengan dukungan kekuasaan, Mu’tazilah melakukan inquisi, memaksa kaum Tradisionalis untuk mengadopsi cara fikir rasional. Disiksa dan dipenjarakan, Ibn Hanbal terus melawan. Perdebatan teologis, seperti di bawah ini, adalah ekspresi dari konflik keras kedua kelompok tersebut. Nama lain yang mereka sukai adalah ahlul hadith, karena mereka sangat menjunjung tinggi Hadith Nabi. Lagi-lagi nama ini muncul di bawah pengaruh Ahmad ibn Hanbal. Untuk membatasi peran akal, posisi Hadith diperkuat. Tidak heran kalau mereka, walupun menolak apapun, termasuk madhhab-madhhab fiqh yang salah satunya adalah Hanbaliyyah, yang datang setelah abad ke 2 H/8 M., diidentikkan dengan Hanbaliyyah. 1. Sifat Tuhan Konsep tauhid dalam Islam terutama dikemukakan dalam syahadat pertama dari dua kalimah syahadat, ashadu alla ilaha illallah (aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah). La ilaha illallah adalah formulasi yang mengandung penafian (nafy) semua tuhan dan pengukuhan (ithbat) Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Tapi siapakah Tuhan itu? Pertanyaan ini diajukan oleh orang-orang musyrik kepada Nabi: “Coba jelaskan Tuhanmu kepada kami!” Menjawab pertanyaan ini, Tuhan mewahyukan Surat al-Ikhlas kepada Nabi[2]. “Katakanlah Allah itu Esa. Allah tempat bergantung. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Dan tidak ada satupun yang menyamainya.” Semua aliran pemikiran dalam Islam setuju bahwa Tuhan itu Esa, tapi tentang apa makna keesaan Tuhan tersebut mereka berbeda. Perbedaan itu antara lain disebabkan oleh firman Tuhan yang menyatakan bahwa Dia itu memiliki NamaNama Yang Baik (al-asma ` al-husna) (QS. 7:180; 17:110; 20:8). Dari nama-nama ini berkembanglah konsep sifat. Sementara ‘nama’ adalah deskripsi tentang Tuhan seperti disebutkan dalam al-Qur’an, sifat adalah kualitas abstrak yang ada di balik nama itu. Yang menjadi masalah adalah hubungan antara sifat Tuhan tersebut dengan dhatNya. Apakah sifat-sifat Tuhan tersebut ada dalam dhzatNya atau diluar dhatNya? Kalau ada dalam dhatNya, apakah akan ada dualisme di dalam diri Tuhan? Kalau sifat tuhan itu kekal seperti halnya dhatNya, apakah berarti akan ada dua kekekalan dalam diri Tuhan? Atau apakah sifat Tuhan itu sama dengan dzat Tuhan? Tuhan adalah sifatNya dan sifatNya adalah Tuhan? Kalau sifat Tuhan tersebut berada di luar dhatNya, apakah berarti Tuhan bergantung kepada sesuatu yang ada di luar diriNya? Demi menjaga keesaan Tuhan, Wasil b. ‘Ata’ (w. 748) menolak keberadaan sifat Tuhan. Menurutnya, “Siapa saja yang menetapkan adanya sifat Tuhan yang kekal berarti dia telah menetapkan adanya dua Tuhan (man athbata sifah qadimah faqad athbata ilahayn)."[3] Dalam pandangannya, juga dalam pandangan kelompoknya Mu’tazilah, meyakini adanya sifat Tuhan adalah shirik (politheisme). Bagi Mu’tazilah, jika memang sifat-sifat Tuhan berbagai keabadian dengan Tuhan, maka ia juga akan berbagi ketuhanan denganNya.[4] Tuhan yang Esa adalah Tuhan yang tidak memiliki sifat. Tuhan mengetahui bukan dengan sifatNya tetapi dengan dzatNya,[5] atau, dengan meminjam kata-kata Abu al-Hudhayl (w. 840), tokoh lain Mu’tazilah, “Pengetahuan Tuhan adalah Tuhan itu sendiri (inna ‘ilm Allah huwa Allah).[6] Karena pandangannya tentang sifat Tuhan yang sangat ketat inilah kelompok Mu’tazilah menyebut dirinya sebagai “pendukung tauhid” (as-hab al-tawhid),[7] mirip dengan nama yang dipakai kelompok Wahhabi yang secara prinsipil bertentangan dengan Mu’tazilah. Bagi kalangan Tradisionalis pandangan Mu’tazilah tersebut tidak lebih dari membuat Tuhan sebagai sesuatu yang kosong. “Mu’tazilah telah membersihkan Tuhan dari semua isiNya dan menjadikanNya tidak memuaskan bagi kesadaran keagamaan.”[8] Kaum Tradisionalis tetap berpandangan bahwa Tuhan itu memiliki sifat yang abadi, namun keabadian sifat Tuhan dan keabadian Tuhan tidak menjadikan adanya dua keabadian. Ahmad b. Hanbal memberikan analogi untuk menjelaskan kesatuan Tuhan dengan sifatNya ini. Seperti pohon palm, demikian katanya. Walaupun memiliki batang, ranting, daun dan sebagainya, namanya masih tetap satu yaitu pohon palem dengan semua bagian-bagiannya. “Demikian halnya Tuhan,” tegasnya.[9] Setelah melalui diskusi yang sangat panjang, hubungan Tuhan dan sifatNya tersebut diformulasikan sebagai “Sifat Tuhan tersebut bukan Tuhan dan juga bukan-bukan Tuhan (hiya la huwa wa-la ghayruh).” Formulasi ini merupakan bagian dari orthodoxi Islam. Namun formulasi yang dikemukakan Mu’tazilah dan Tradisionalis ini masih mendapat kritikan dari al-Sijistani, seorang Isma’ili yang wafat tahun 971. Dia yakin bahwa semua formulasi tentang keesaan Tuhan pada akhirnya akan berakhir dengan kegagalan, karena akan terjerumus kalau tidak pada tashbih (menyamakan Tuhan dengan manusia seperti dalam kasus kaum Tradisionalis) pada (pengosongan Tuhan seperti kasus Mu’tazilah). Bahkan al-Sijistani mengemukakan bahwa ta’til pada dasarnya tashbih yang tersembunyi karena ia masih menyamakan Tuhan dengan apa yang ada dalam pikiran manusia. Lebih lanjut al-Sijistani mengemukakan bahwa jika ingin mensucikan tauhid dan membebaskan diri dari shirik, seseorang harus menegasikan ta’til, atau menegasikan negasi tashbih sehingga dia menjadi negasi ganda.[10] Semangat dari negasi ganda ini adalah bahwa keesaan Tuhan, bahkan apapun tentang Tuhan, tidak bisa dicakup oleh satu deskripsi tertentu. Menetapkan sifat Tuhan seperti kalangan Tradisionalis tidak benar. Sama tidak benarnya adalah menafikan sifat Tuhan seperti yang dilakukan Mu’tazilah. Semua gambaran tentang Tuhan pada akhirnya hanya akan membatasi Tuhan sebab “bahasa manusia hanya syah dipakai untuk membicarakan apa-apa yang ada di wilayah manusia dan hanya Tuhan yang bisa berbicara tentnag diriNya kepada mansia karena bahasa manusia tidak cukup.”[11] 2. Penciptaan Alam Menerima keesaan Tuhan berarti menerima Tuhan sebagai satu-satunya pencipta. Dia adalah sumber dari segala ciptaan, meliputi benda dan kejadian. Bahwa kekuatan mencipta dihubungkan dengan keesaan Tuhan bisa dilihat, misalnya, dalam QS. 35:3, dan bahwa ciptaanNya itu meliputi segala hal bisa dilihat, misalnya, dalam QS 54:49. Kedua kata ‘menciptakan (khalaqa)’ dan ‘ukuran (qadar)’ yang ditemukan dalam ayat itu mengandung arti bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada.[12] Semua aliran pemikiran dalam Islam setuju bahwa Tuhanlah satu-satunya pencipta, namun mereka berbeda dalam memahami bagaimana prosesnya dan apa yang dimaksud ‘segala sesuatu’ itu. Termasuk ke dalam masalah yang pertama adalah proses penciptaan alam, sementara ke dalam masalah yang kedua adalah sumber dari perbuatan dan kehendak manusia, serta nilai. Seperti yang akan dijelaskan di bawah, ketiga masalah ini juga terkait erat dengan konsep monotheisme. Tentang penciptaan alam. Maslahnya adalah bagaimana Tuhan yang abstrak, simple dan transenden menjkadi sumber dari dari alam yang nyata dan sangat beragam ini. Al-Farabi (w. 950) menjawab pertanyaan ini dengan konsep emanasi (al-fayd). Menurutnya segala sesuatu yang ada di alam ini memancar dari Tuhan dengan sendirinya “bukan karena pilihan dan kehendak manusia” dan “bukan tujuan Tuhan.” Dengan cara yang natural ini al-Farabi menjelaskan keberadaan 10 akal dan planet.[13] Tetapi, jika alam ini memancar dari Tuhan, maka dia akan ada sepanjang Tuhan ada. Karena Tuhan abadi, maka alam yang memancar dariNya juga akan abadi. Al-Ghazzali (w. 1111) mengkritik pemikiran ini dan mengangapnya ‘kafir’,[14] sebuah istilah yang pertama kali dipakai untuk menyebut orang-orang Mekah yang menolak mengakui keesaan Tuhan dan mempertahankan kepercayaan politheistik. 3. Perbuatan Manusia Dalam masalah ini, masyarakat Muslim terbagi menjadi tiga kelompok besar Jabbariyyah, Qadariyyah/Mu’tazilah dan Tradisinionalis. Dalam pandangan Jabbariyyah semua perbuatan manusia –baik atau buruk—semuanya berasal dari Tuhan. Tokoh utama aliran ini adalah Jahm b. Safwan (w. 745-6). Menurutnya, manusia tidak memiliki kekuasaan apa-apa atas apapun, mereka tidak memiliki sifat mampu (istita’ah), tetapi dipaksa untuk melakukan segala perbuatannya; mereka tidak punya kekuatan, kehendak atau pilihan.[15] Akibat dari keimanan kepada keesaan Allah sebagai satu-satunya pencipta dan pemilik dari segala sesuatu termasuk perbuatan manusia, Jahm dan pengikutnya menolak kebebasan manusia. Aliran Qadariyyah/Mu’tazilah berpendapat sebaliknya. Bagi mereka, manusia memiliki kontrol terhadap perbuatannya. Wa>s}il b. ‘At}a>’, salah seorang tokohnya, berpendapat bahwa manusia adalah pemilik perbuatannya, baik atau buruk, iman atau kufur, ta’at atau maksiat; dialah pelakunya.[16] Dalam teologi Mu’tazilah, persoalan ini biasanya didiskusikan di dalam rubrik “keadilan Tuhan”: Manusia harus bebas menentukan pilihan kalalau mereka harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan, jika Tuhan adil, Dia tidak bisa disifati dengan kejahatan dan kezaliman, dan Dia tidak bisa meminta manusia untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintahNya.[17] Di mata kaum Tradisionalis pandangan Mu’tazilah tersebut bukan hanya membatasi kebebasan Tuhan (bahwa Dia tidak bisa meminta manusia untuk melakukan sesuatu …), juga bertentangan dengan keesaan Tuhan. Keesaan Tuhan mengharuskan adanya keesaan perbuatan, dhat dan sifat.[18] Keesaan dalam perbuatan berarti “tidak satupun makhluk yang memiliki suatu perbuatan, karena Tuhanlah Pencipta dari perbuatan segala sesuatu yang diciptakanNya, Nabi, malaikat, dan yang lainnya.”[19] Mengingkari Tuhan sebagai sumber kejahatan berarti mengakui adanya sumber dari sesuatu selain Tuhan, atau mengakui manusia sebagai pencipta perbuatannya sama saja dengan mengakui adanya pencipta selain Tuhan. Ini musyrik. Bagaimana dengan kenyataan bahwa manusia sesungguhnya bisa menentukan perbuatannya sendiri? Untuk memecahkannya, al-Ash’ari (w. 935-6), tokoh yang diidentikan dengan Ahlussunnah wal-Jama’ah, dan para pengikutnya mengembangkan konsep iktisab, dimana hubungan antara tindakan yang diciptakan Tuhan dan tanggung jawab manusia dijembatani. 4. Sumber Nilai Jika Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu, Dia juga adalah satu-satunya Dzat yang menentukan nilai dari segala sesuatu (baik atau buruk) melalui wahyu kepada nabi-nabiNya. Dalam muqaddimah bukunya al-Ibanah, al-Ash’ari menegaskan bahwa melalui nabi-nabiNya Tuhan menginformasikan kepada kita shari’at, hukum, halal dan haram.[20] Pandangan ini dianut oleh kalangan Tradisionalis, yang bisa disebut sebagai pengikut subjektifisme theistik: Baik dan buruk dan sejenisnya tidak memiliki arti lain selain yang dikehendaki Tuhan.[21] Pandangan ini sama sekali bersebrangan dengan objektifisme yang dianut Mu’tazilah: Nilai seperti keadialn dan kebaikan memiliki eksistensi tersendiri yang independen dari kemauan siapapun, termasuk Tuhan.[22] Tetapi pandangan manapun yang diambil, tetap menyisakan persoalan. Meyakini Tuhan sebagai satu-satunya pemberi nilai memunculkan masalah seperti “Kenapa Tuhan mesti tidak menyukai keburukan yang berasal dariNya?” dan, sebaliknya, meyakini independensi nilai sama saja dengan mengakui adanya sumber nilai selain Allah. 5. Monisme Masalah lain yang juga potensial untuk dinggap ‘merusak’ tauhid ada dari kalangan sufi terutama pandangan mereka yang monistik serta pemujaan terhadap orang suci. Monisme cenderung menafikan pemisahan antara Tuhan dan ciptaanNya. Dalam pandangan ini semua realitas, termasuk manusia, ada dalam wilayah Tuhan. Ibn ‘Arabi, misalnya, berpandangan bahwa eksistensi ciptaan Tuhan tidak lain dari esensi eksistensi Penciptanya.[23] Bisa jadi dengan kata-katanya ini Ibn ‘Arabi justeru hendak menegaskan keesaan Tuhan: Karena hanya Tuhan yang ada maka apapun selainNya ada dalam keberadaan Tuhan. Di kalangan Tradisionalis pandangan ini bertubrukan dengan konsep keesaan Tuhan dimana Pencipta dan makhluk ciptaanNya sama sekali berbeda. Tidak mungkin dalam diri pencipta ada benda-benda yang diciptakannya yang banyak ini. “Berbeda dengan ciptaaNya (mukhalafah li-al-hawadith)” adalah salah satu dari 21 sifat Tuhan yang diyakini Ahlu Sunnah wa al-Jama’ah. Atas dasar ini kalangan Tradisionalis menolak ajaran Sufi papapun yang bisa membawa pada penyatuan antara Tuhan dengan hambanya seperti konsep kesatuan wujud (wihdat alwujud). 6. Pemujaan Orang Suci Dalam sufisme, fungsi orang suci (syaikh) adalah untuk membimbing para pengikutnya ke jalan sufi yang benar. Sebelum masuk ke dalam suatu aliran sufi, seseorang biasanya akan melakukan bay’at, suatu penyerahan diri sepenuhnya kepada gurunya dalam menpapai ketinggian spiritual. Hal ini bisa menumbuhkan pandangan bahwa gurunya adalah satu-satunya mediator yang bisa menghubungkan dirinya dengan Tuhan. Lewat para sufilah Tuhan disembah. Masyarakat Muslim bisa terjerumus pada shirik, sebab bisa jadi, ketika beribadah, yang lebih kuat muncul justeru bayangan guru sufinya ketimbang Tuhan. Meuurut Ignaz Goldziher, dalam perkembangannya, orang-orang suci tersebut menjadi medium dimana keyakinan politheistik diekspresikan.[24] Kalau ini benar, maka hak Tuhan sebagai Dzat yang patut disembah terkurangi oleh keberadaan para orang suci dari kalangan sufi tersebut. Wahhabisme dan Kelelahan Intelektual Sekali lagi, diskusi tentang masalah-masalah tersebut diatas menujukkan bahwa semua kalangan, baik teolog, filosof, sufi masupun Tradisionalis, mengalami kesulitan untuk menjelaskan keesaan Tuhan. Semua deskripsi yang mereka berikan pada akhirnya reduktif dan membatasi keberadaan Tuhan. Posisi apapun yang diambil, deskripsi apapun yang dipilih, tetap problematik. Ibn Hanbal, juga Ibn Taymiyyah dan Ibn ‘Abd al-Wahhab, sangat merasakan betapa perdebatan ini tidak akan berujung dan mengandung banyak lubang yang bisa menjerumuskan masyarakat Muslim pada kemusyrikan. Mereka memutuskan untuk tidak melanjutkannya, paling tidak bagi orang lain. Mereka lelah. Mereka mengkritik dengan pedas kelompok teolog, filosof dan kelompok sufi. Dengan sendirinya, ketika penafsiran ditutup, ketika kekhawatiran sesat yang berlebihan muncul, maka yang akan dianut adalah kebenaran literal al-Qur’an. Kelompok Fundamentalis sangat tidak mempercayai akal dalam tradisi beragama. Pandangan mereka kepada manusia sangat negatif: bahwa pada dasarnya manusia tidak akan mampu mencari kebenaran sendiri. Kebenaran tidak dicari, tapi diberikan oleh al-Qur’an. Kalau tidak jelas, maka penjelasannya harus dilihat dalam Hadith Nabi. Hadith Nabi, dengan demikian, menempati posisi yang sangat penting dalm gerakan fundamentalisme. Sebagaimana al-Qur’an, hadithpun dilihat sebagai system yang tertutup dan statis. Kebenaran sudah diformulasikan dengan sempurna oleh generasi Salaf, yang hidup sampai abad ke-2 H/8 M. Apapun yang muncul setelah masa itu termasuk madhhab-madhab dalam Islam akan ditolak dan bisa dengan mudah dicap sebagai bid’ah. Ketika menekankan pentingnya Islam pada abad ke-2/8 M., sebelum ramburambu penafsiran dibangun para imam madhhab dan kemudian mempersempit ruang gerak masyarakat Muslim, kelompok Wahhabiyah sesungguhnya ada pada posisi yang sama dengan kelompok Islam liberal (baca: JIL). Kelompok yang terakhir ini, karena ingin mendapatkan ruang yang lebih besar untuk mengekpresikan keberagamaan mereka dan untuk menjadikan Islam kembali lincah dan fleksibel dalam menghadapi persoalan yang demikian kompleks, berusaha merampingkan Islam dengan mengembalikan Islam kepada prinsipprinsip dasarnya. Yang muncul adalah Islam dan masyarakat Islam awal: Salaf. Ini juga yang ada dalam banyangan aliran Wahhabisme. Perbedaannya, sementara kelompok Islam liberal memperlakukan kerampingan Islam itu secara terbuka, Wahhabi mematikannya. Keadaan yang bertolak belakangpun muncul. Ketika diperlakukan secara dinamis, Islam yang sudah ‘diperkecil’ memiliki ruang yang sangat lebar untuk dimasuki benda-benda baru yang ditemukan sekarang. Sebaliknya, Islam yang ‘sudah diperkecil’ lalu dimatikan tidak akan mampu menampung benda-benda baru tersebut. Tidak ada ruang di dalamnya. Seperti memasukkan gajah ke lubang semut. Semua kelompok muslim, baik dari kalangan teolog, filosof, sufi, Muhammadiyah, NU, Wahhabis, JIL, dll., pada dasarnya sedang melakukan hal yang sama: memahami Islam dan mengamalkannya dengan baik untuk dirinya dan untuk masyarakatnya. Mereka semua sedang menangkap pesan-pesan Allah yang Maha Luas, Yang tak terbatas, sementara semua merekia mengakui keterbatasan diri mereka masing-masing. Jangan sampai ada satu keterbatasan dipakai untuk membatasi yang tak terbatas. Semua model penafsiran pada akhirnya relatif. Bisa jadi suatu saat mereka kelelalahan dan memutuskan untuk membangun rumah Islam di suatu tempat bagi dirinya. Tapi jangan sampai kelelalan itu diwariskan kepada orang lain dan memaksa orang lain untuk tinggal di rumahnya.[] Kembali Ke Atas | Depan | Tokoh | Kolom | Diskusi | Wawancara | Situs | E-Books | Kliping | Tanggapan | Tentang Kami | Kontak | Jaringan | Hak Cipta (C) Jaringan Islam Liberal 2002