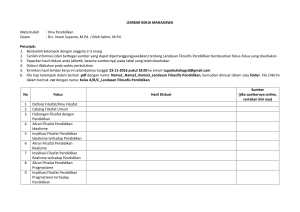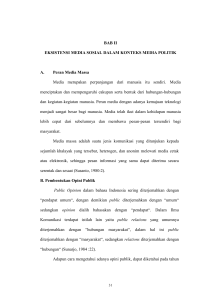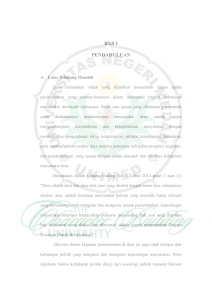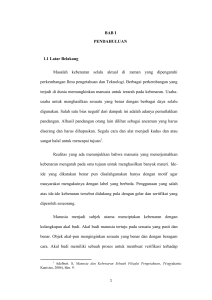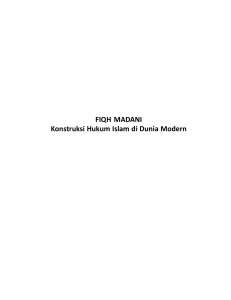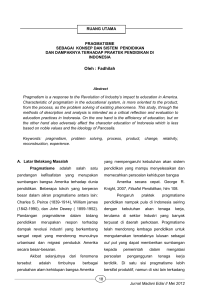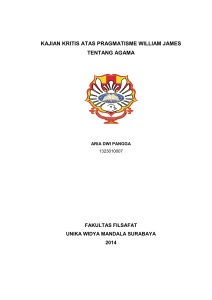FILSAFAT HUKUM BARAT DAN PENGARUHNYA TERHADAP
advertisement

FILSAFAT HUKUM BARAT DAN PENGARUHNYA TERHADAP TEORI HUKUM ISLAM (Interelasi Filsafat Pragmatisme Charles S. Peirce dan Rumusan Maqashid al-Syari’ah al-Syatibi) Dr. Didi Kusnadi, S.Ag Pendahuluan Sejak runtuhnya Dinasti Islam Turki Ustmani, perhatian kalangan orientalis Barat dalam mengkaji hukum Islam diwujudkan dalam bentuk mempelajari, menyelidiki, menterjemahkan, mengkaji dan menertibkan terhadap berbagai buku fikih standar. Salah satu bentuk karya orientalis Barat dalam menelusuri kajian-kajian hukum Islam adalah Revue Internationale de Droit Compare (Majalah Internasional Untuk Hukum Perbaningan) di Perancis. Bahkan para sarjana hukum Barat seperti Kohler dari Jerman, Wignore dan Delvechis dari Amerika telah mengakui bahwa adanya fleksibilitas dan universalitas hukum Islam mampu merespon perkem-bangan masyarakat sepanjang masa, dan berani mensejajarkan hukum Islam dengan hukum Romawi dan Inggris di berbagai negara. Hal ini diakui oleh Lambert seorang sarjana hukum Perancis dalam seminar internasional untuk perbandingan hukum pada 1932. Di kalangan pemikir hukum Islam muncul suatu sikap kritis untuk membangun konsep hukum Islam agar senantiasa relevan dengan kebutuhan zaman. Sebut saja, salah satunya al-Syatibi. Ia dikenal sebagai bapak maqashid al-syari’ah. Teori maqashid al-syari’ah al-syatibi kini telah banyak dikembangkan oleh pemikir hukum modern. Namun di saat bersamaan, kalangan pemikir hukum Islam modern juga mengakui bahwa persoalan mendasar saat ini adalah kesulitan merumuskan metodologi hukum yang tepat agar hukum Islam bisa berlaku secara keseluruhan. Hampir di sebagian besar negara Muslim yang menerapkan hukum Islam selalu melahirkan konflik sosial. Bahkan konflik bukan hanya antara Muslim dengan Muslim, melainkan pula antara Muslim dan Non Muslim. Atas dasar itu, kini banyak pemikir hukum Islam yang mencoba membongkar tradisi hukum Islam sebelumnya – yang dibangun dari ijtihad – dengan pemikiran baru yang berasal dari Barat. Pada gilirannya, terjadilah pergeseran norma hukum Islam di masyarakat karena masuknya pengaruh hukum Barat tersebut. Sebagai contoh, tulisan ini akan menjelaskan masuknya filsafat ajaran pragmatisme ke dalam proses pengembangan hukum dan perundang-undangan Islam di negara-negara Muslim. 1 Memperkenalkan Filsafat Pragmatisme Istilah Pragmatisme berasal dari kata Yunani pragma yang berarti perbuatan (action) atau tindakan (practice). Isme di sini sama artinya dengan isme-isme lainnya, yaitu berarti aliran atau ajaran atau paham. Dengan demikian Pragmatisme itu berarti ajaran yang menekan¬kan bahwa pemikiran itu menuruti tindakan.Pragmatisme memandang bahwa kriteria kebenaran ajaran adalah “faedah” atau “manfaat”. Suatu teori atau hipotesis dianggap oleh Pragmatisme benar apabila membawa suatu hasil. Dengan kata lain, suatu teori itu benar kalau berfungsi (if it works). Dari pengertian di atas, dapat diambil sebuah pengertian bahwa Pragmatisme masuk ke dalam pembahasan teori kebenaran (the theory of truth), sebagaimana yang nampak menonjol dalam pandangan William James, terutama dalam bukunya The Meaning of The Truth (1909). Kebenaran menurut James adalah sesuatu yang terjadi pada ide, yang sifatnya tidak pasti. Sebelum seseorang menemukan satu teori berfungsi, tidak diketahui kebenaran teori itu. Atas dasar itu, kebenaran itu bukan sesuatu yang statis atau tidak berubah, melainkan tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu. Kebenaran akan selalu berubah, sejalan dengan perkembangan pengalaman, karena yang dikatakan benar dapat dikoreksi oleh pengalaman berikutnya. Dalam The Meaning of The Truth (1909), James menjelaskan metode berpikir yang mendasari pandangannya di atas. Dia mengartikan kebenaran itu harus mengandung tiga aspek. Pertama, kebenaran itu merupakan suatu postulat, yakni semua hal yang di satu sisi dapat ditentukan dan ditemukan berdasarkan pengalaman, sedang di sisi lain, siap diuji dengan perdebatan atau diskusi. Kedua, kebenaran merupakan suatu pernyataan fakta, artinya ada sangkut pautnya dengan pengalaman. Ketiga, kebenaran itu merupakan kesimpulan yang telah diperumum (digeneralisasikan) dari pernyataan fakta. Dari ketiga point tersebut, William James dapat dilihat sebagai penganjur Empirisme dengan cara berpikir induktif. Menurut James, pemikir Rasionalis adalah orang yang bekerja dan menyelidiki sesuatu secara deduktif, dari yang menyeluruh ke bagian-bagian. Rasionalis berusaha mendeduksi yang umum ke yang khusus, mendeduksi fakta dari prinsip. Sedangkan pemikir Empirisme, berangkat dari fakta yang khusus (partikular) kepada kesimpulan umum yang menyeluruh. Seorang Empiris membuat generalisasi dari induksi terhadap fakta-fakta yang partikular. 2 Tetapi Empirisme William James adalah ”Empirisme Radikal”, berbeda dengan empirisme tradisional yang kurang memperhatikan hubungan-hubungan antar fakta. Empirisme radikal melihat bahwa hubungan yang mempertautkan pengalaman-pengalaman, harus merupakan hubungan yang dialami. Pragmatisme yang diserukan oleh James disebut Practicalisme, sebenarnya merupakan perkembangan dan olahan lebih jauh dari Pragmatisme Peirce. Hanya saja, Peirce lebih menekankan penerapan Pragmatisme ke dalam bahasa, yaitu untuk menerangkan artiarti kalimat sehingga diperoleh kejelasan konsep dan pembedaannya dengan konsep lain. Dia menggunakan pendekatan matematik dan logika simbol (bahasa), berbeda dengan James yang menggunakan pendekatan psikologi. Dalam memahami kemajemukan kebenaran (pernyataan), Peirce membagi kebenaran menjadi dua. Pertama adalah Trancendental Truth, yaitu kebenaran yang bermukim pada benda itu sendiri. Yang kedua adalah Complex Truth, yaitu kebenaran dalam pernyataan. Kebenaran jenis ini dibagi lagi menjadi kebenaran etis atau psikologis, yaitu keselarasan pernyataan dengan apa yang diimani si pembicara, dan kebenaran logis atau literal, yaitu keselarasan pernyataan dengan realitas yang didefinisikan. Semua kebenaran pernyataan ini, harus diuji dengan konsekuensi praktisnya melalui pengalaman. John Dewey diketahui mengembangkan lebih jauh Pragmatisme James. Jika James mengembangkan Pragmatisme untuk memecahkan masalah-masalah individu, maka Dewey mengembangkan Pragmatisme dalam rangka mengarahkan kegiatan intelektual untuk mengatasi masalah sosial yang timbul di awal abad ini. Dewey menggunakan pendekatan biologis dan psikologis, berbeda dengan James yang tidak menggunakan pendekatan biologis. Dewey menerapkan Pragmatismenya dalam dunia pendidikan Amerika dengan mengembangkan suatu teori problem solving, yang mempunyai langkah-langkah sebagai berikut: 1. Merasakan adanya masalah. 2. Menganalisis masalah itu, dan menyusun hipotesis-hipotesis yang mungkin. 3. Mengumpulkan data untuk memperjelas masalah. 4. Memilih dan menganalisis hipotesis. 5. Menguji, mencoba, dan membuktikan hipotesis dengan melakukan eksperimen/pengujian. Meskipun berbeda-beda penekanannya, tetapi ketiga pemikir utama Pragmatisme menganut garis yang sama, yakni kebenaran suatu 3 ide harus dibuktikan dengan pengalaman. Demikianlah Pragmatisme berkhotbah dan menggurui dunia, bahwa yang benar itu hanyalah yang mempengaruhi hidup manusia serta yang berguna dalam praktik dan dapat memenuhi kebutuhan manusia. Dari pemaparan di atas, bisa dikatakan bahwa Pragmatisme adalah aliran yang mengukur kebenaran suatu ide dengan kegunaan praktis yang dihasilkannya untuk memenuhi kebu-tuhan manusia. Ide semacam ini keliru jika dilihat dari tiga sisi. Pertama, Pragmatisme mencampur adukkan kriteria kebenaran ide dengan kegunaan praktisnya. Kebenaran suatu ide adalah satu hal, sedang kegunaan praktis ide itu adalah hal lain. Kebenaran sebuah ide diukur dengan kesesuaian ide itu dengan realitas, atau dengan standar-standar yang dibangun di atas ide dasar yang sudah diketahui kesesuaiannya dengan realitas. Sedang kegunaan praktis suatu ide untuk memenuhi hajat manusia, tidak diukur dari keberhasilan penerapan ide itu sendiri, tetapi dari kebenaran ide yang diterapkan. Maka, kegunaan praktis ide tidak mengandung implikasi kebenaran ide, tetapi hanya menunjukkan fakta terpuaskannya kebutuhan manusia. Kedua, Pragmatisme menafikan peran akal manusia. Menetapkan kebenaran sebuah ide adalah aktivitas intelektual dengan menggunakan standar-standar tertentu. Sedang penetapan kepuasan manusia dalam pemenuhan kebutuhannya adalah sebuah identifikasi instinktif. Memang identifikasi instinktif dapat menjadi ukuran kepuasan manusia dalam pemuasan hajatnya, tapi tak dapat menjadi ukuran kebenaran sebuah ide. Maka, Pragmatisme berarti telah menafikan ak¬tivitas intelektual dan menggantinya dengan identifikasi instinktif. Atau dengan kata lain, Pragmatisme telah menundukkan keputusan akal kepada kesimpulan yang dihasilkan dari identifikasi instinktif. Ketiga, Pragmatisme akan menimbulkan relativitas dan kenisbian kebenaran sesuai dengan perubahan subjek penilai ide – baik individu, kelompok, dan masyarakat – dan perubahan konteks waktu dan tempat. Dengan kata lain, kebenaran hakiki Pragmatisme baru dapat dibuktikan – menurut Pragmatisme itu sendiri – setelah melalui pengujian kepada seluruh manusia dalam seluruh waktu dan tempat. Keadaan ini mustahil dan tak akan pernah terjadi. Maka, Pragmatisme berarti telah menjelaskan inkonsistensi internal yang dikandungnya dan menafikan dirinya sendiri. Pragmatisme adalah aliran pemikiran yang memandang bahwa benar tidaknya suatu ucapan, dalil, atau teori, semata-mata bergantung kepada berfaedah atau tidaknya ucapan, dalil, atau teori tersebut bagi manusia untuk bertindak dalam kehidupannya. Ide ini merupa¬kan 4 budaya dan tradisi berpikir Amerika khususnya dan Barat pada umumnya, yang lahir sebagai sebuah upaya intelektual untuk menjawab problem-problem yang terjadi pada awal abad ini. Pragmatisme mulai dirintis di Amerika oleh Charles S. Peirce (1839-1942), yang kemudian dikembangkan oleh William James (1842-1910) dan John Dewey (18591952). Pragmatisme tak dapat dilepaskan dari keberadaan dan perkembangan ide-ide sebelumnya di Eropa. Tak dapat diingkari pula bahwa adanya pengaruh dan imbas balik Pragmatisme terhadap ide-ide yang dikembangkan lebih lanjut di Eropa. William James mengatakan bahwa Pragmatisme yang diajarkannya, merupakan “nama baru bagi sejumlah cara berpikir lama”. Ia sendiri pun menganggap pemikirannya sebagai kelanjutan dari Empirisme Inggris, seperti yang dirintis oleh Francis Bacon (1561-1626), yang kemudian dikembangkan oleh Thomas Hobbes (1558-1679) dan John Locke (1632-1704). Selama berabad-abad, Pragmatisme telah mempengaruhi filsafat Eropa dalam berbagai bentuknya, baik filsafat Eksistensialisme maupun Neorealisme dan Neopositivisme. Pragmatisme, telah menjadi semacam ruh yang menghidupi tubuh ide-ide dalam ideologi Kapitalisme, yang telah disebarkan Barat ke seluruh dunia melalui penjajahan dengan gaya lama maupun baru. Dalam konteks inilah, Pragmatisme dapat dipandang berbahaya karena telah mengajarkan dua sisi kekeliruan sekaligus kepada dunia yakni standar kebenaran berfikir dan berbuat bagi manusia. Atas dasar itu, mereka yang bertanggung jawab terhadap kemanusiaan tak dapat mengelak dari sebuah tugas mulia yang menantang, yakni menelaah lebih kritis ajaran filsafat Pragmatisme sebagai landasan strategis untuk melakukan dekonstruksi (penghancuran bangunan ide) Pragmatisme sebaiknya dijadikan alat untuk mengkonstruk ideologi dan peradaban Islam sebagai alternatif dari Kapitalisme yang telah mengalami pembusukan dan hanya menghasilkan penderitaan pedih bagi umat manusia. Secara ontologis, Pragmatisme akan diawali dengan penjelasan ringkas tentang sejarah mata rantai pemikiran Barat, agar diperoleh gambaran komprehensif tentang posisi Pragmatisme dalam konstelasi pemikiran Barat. Setelah melalui Abad Pertengahan (abad V-XV M) yang gelap dengan ajaran gereja yang dominan, Barat mulai menggeliat dan bangkit dengan Renaissance, yakni suatu gerakan atau usaha –yang berkisar antara tahun 1400-1600 M– untuk menghidupkan kembali kebu¬dayaan klasik Yunani dan Romawi. Berbeda dengan tradisi Abad 5 Pertengahan yang hanya mencurahkan perhatian pada masalah metafisik yang abstrak, seperti masalah Tuhan, manusia, kosmos, dan etika, Renaissance telah membuka jalan ke arah aliran Empirisme. William Ockham (1285-1249) dengan filsafat Gulielmus-nya yang mendasarkan pada pengenalan inderawi, telah mulai menggeser dominasi filsafat Thomisme, ajaran Thomas Aquinas yang meno¬njol di Abad Pertengahan, yang mendasarkan diri pada filsafat Aristoteles. Ide Ockham ini dianggap sebagai benih awal bagi lahirnya gerakan Renaissance. Semangat gerakan Renaissance ini, sesungguhnya terletak pada upaya pembebasan akal dari kekangan dan belenggu gereja dan menjadikan fakta empirik sebagai sumber pengetahuan, tidak terletak pada filsafat Yunani itu sendiri. Dalam pada itu, Barat hanya mengambil karakter utama pada filsafat dan seni Yunani, yakni keterlepasannya dari agama, atau dengan kata lain, adanya kebebasan kepada akal untuk berkreasi. Ini terbukti antara lain dari ide beberapa tokoh Renaissance, seperti Nicolaus Copernicus (1473-1543) dengan pandangan heliosentriknya, yang didukung oleh Johanes Kepler (1571-1630) dan Galileo Galilei (1564-1643). Juga Francis Bacon (1561-1626) dengan teknik berpikir induktifnya, yang berbeda dengan teknik deduk¬tif Aristoteles (dengan logika silogismenya) yang diajarkan pada Abad Pertengahan. Jadi, Barat tidak mengambil filsafat Yunani apa adanya, sebab justru filsafat Yunani itulah yang menjadi dasar filsafat Kristen pada Abad Pertengahan, baik periode Patristik (400-1000 M) dengan filsafat Emanasi Neoplatonisme yang dikembangkan oleh Augustinus (354-430), maupun periode Scholastik (1000-1400 M) dengan filsafat Thomisme yang bersandar pada Aristoteles. Semua filsafat Yunani ini membahas metafisika, tidak membahas fakta empirik sebagaimana yang dituntut oleh Renaissance. Jadi, semangat Renaissance itu tidak bersumber pada filsafat Yunaninya itu sendiri, tetapi pada karakternya yang terlepas dari agama. Pragmatisme dan Renaissance di Eropa Renaissance juga diperkuat adanya Reformasi, sebuah upaya pemberontakan terhadap dominasi gereja Katholik yang dirintis oleh Marthin Luther di Jerman (1517). Gerakan ini bertolak dari korupsi umum dalam gereja – seperti penjualan Surat Tanda Pengampunan Dosa (Afllatbrieven), penindasannya yang telanjang, dan dominasinya terhadap negara-negara Eropa. Meskipun Reformasi tidak secara langsung ikut memperjuangkan apa yang disebut “pembebasan akal”, tetapi gerakan ini 6 secara tak sadar telah memperkuat Renasissance dengan mempelopori kebebasan beragama (Protestan) dan telah memperlemah posisi Gereja dengan memecah kekuatan Gereja menjadi dua aliran; Katholik dan Protestan. Kritik-kritik terhadap Injil di Jerman sekitar abad XVII juga dianggap implikasi tak langsung dari adanya Reformasi. Meskipun demikian, Gereja Katholik dan tokoh Reformasi memiliki sikap sama terhadap upaya Renaissance, yakni menentang ide-ide yang tidak sesuai dengan Injil. Calvin, seorang tokoh Reformasi di Jenewa (Swiss), mendukung pembakaran hidup-hidup terhadap Servetus dari Spanyol (1553), yang menentang Trinitas. Gereja Katholik dan Reformasi juga sama-sama menolak ide Copernicus (1543) tentang matahari sebagai pusat tatasurya, seraya mempertahankan doktrin Ptolemeus yang menganggap bumi sebagai pusat tatasurya. Pada abad XVII, perkembangan Renaissance telah melahirkan dua aliran pemikiran yang berbeda: aliran Rasionalisme dengan tokohtokohnya seperti Rene Descartes (1596-1650), Baruch Spinoza (1632-1677), dan Pascal (1623-1662), dan aliran Empirisme dengan tokoh-tokohnya Thomas Hobbes (1558-1679), John Locke (1632-1704). Rasionalisme memandang bahwa sumber pengetahuan yang dapat dipercaya adalah rasio (akal), sedang Empirisme beranggapan bahwa sumber pengetahuan adalah empiri, atau pengalaman manusia dengan menggunakan panca inderanya. Kemudian datanglah Masa Pencerahan (Aufklarung) pada abad XVIII yang dirintis oleh Isaac Newton (1642-1727), sebagai perkembangan lebih jauh dari Rasionalisme dan Empirisme dari abad sebelumnya. Pada abad sebelumnya, fokus pembahasannya adalah pemberian inter¬pretasi baru terhadap dunia, manusia, dan Tuhan. Sedang pada Masa Aufklarung, pembaha¬sannya lebih meluas mencakup segala aspek kehidupan manusia, seperti aspek pemerintahan dan kenegaraan, agama, ekonomi, hukum, pendidikan dan sebagainya. Bertolak dari prinsip-prinsip Empirisme John Locke, George Berkeley (1685-1753) mengembangkan “immaterialisme”, sebuah pandangan yang lebih ekstrim daripada pandangan John Locke. Jika Locke berpandangan bahwa kita dapat mengenal esensi sebenarnya (hakikat) dari fenomena material dan spiritual, Berkeley menganggap bahwa substansi-substansi material itu tidak ada, Yang ada adalah ciri-ciri yang diamati. Pandangan Locke dan Berkeley dikem¬bangkan lebih lanjut oleh David Hume (1711-1776), dengan dua ide pokoknya; yakni tentang skeptisisme (keragu-raguan) ekstrim bahwa filsuf itu mampu menemukan 7 kebenaran tentang apa saja, dan keyakinan bahwa “pengetahuan tentang manusia” akan dapat menjelaskan hakikat pengetahuan yang dimiliki manusia. Selain George Berkeley dan David Hume, Immanuel Kant (17241804) juga dianggap salah seorang tokoh Masa Pencerahan. Filsafat Kant disebut Kritisisme, yakni aliran yang mencoba mensintesiskan secara kritis Empirisme yang dikembangkan Locke yang bermuara pada Empirisme Hume, dengan Rasionalisme dari Descartes. Kant mulai menelaah batas-batas kemampuan rasio, berbeda dengan dengan para pemikir Rasionalisme yang mempercayai kemampuan rasio bulat-bulat. Namun demikian, Kant juga mempercayai Empirisme. Walhasil dia berpandangan bahwa semua pengetahuan mulai dari pengalaman, namun tidak berarti semua dari pengalaman. Obyek luar ditangkap oleh indera, tetapi rasio mengorganisasikan bahan-bahan yang diperoleh dari pengalaman tersebut. Pada abad XIX, filsafat Kant tersebut dikembangkan lebih lanjut di Jerman oleh J. Fichte (1762-1814), F. Schelling (1775-1854) dan Hegel (17701831). Namun yang mereka kembangkan tidaklah filsafat Kant seutuhnya, tetapi lebih memprioritaskan ide-ide, yakni tidak memfokuskan pada pembahasan fakta empirik. Karenanya, aliran mereka disebut dengan Idea¬lisme. Dari ketiganya, Hegel merupakan tokoh yang menonjol, karena banyak pemikir pada abad ke-19 dan ke-20 yang merupakan murid-muridnya, baik langsung maupun tidak. Mereka terbagi dalam dua pandangan, yaitu pengikut Hegel aliran kanan yang membela agama Kristen seperti John Dewey (1859-1952), salah seorang peletak dasar Pragmatisme yang menjadi budaya Amerika (baca : Kapitalisme) saat ini, dan pengikut Hegel aliran kiri yang memusuhi agama, seperti Feuerbach, Karl Marx, dan Engels dengan ide Materialisme yang merupakan dasar ideologi Komunisme di Rusia. Empirisme itu sendiri pada abad XIX dan XX berkembang lebih jauh menjadi beberapa aliran yang berbeda, yaitu Positivisme, Materialisme, dan Pragmatisme. Positivisme dirintis oleh August Comte (1798-1857), yang dianggap sebagai Bapak ilmu Sosiologi Barat. Positivisme sebagai perkembangan Empirisme yang ekstrim, adalah pandan¬gan yang menganggap bahwa yang dapat diselidiki atau dipelajari hanyalah “data-data yang nyata/empirik”, atau yang mereka namakan positif. Nilai-nilai politik dan sosial menurut Posi¬tivisme dapat digeneralisasikan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penyeidikan terhadap kehidupan masyarakat itu sendiri. Nilai-nilai politik dan 8 sosial juga dapat dijelaskan secara ilmiah, dengan mengemukakan perubahan historis atas dasar cara berpikir induktif. Jadi, nilai-nilai tersebut tumbuh dan berkembang dalam suatu proses kehidupan dari suatu masyarakat itu sendiri. Materialisme adalah aliran yang menganggap bahwa asal atau hakikat segala sesuatu adalah materi. Di antara tokohnya ialah Feuerbach (1804-1872), Karl Marx (1818-1883) dan Fredericht Engels (1820-1895). Karl Marx menerima konsep Dialektika Hegel, tetapi tidak dalam bentuk aslinya (Dialektika Ide). Kemudian dengan mengambil Materialisme dari Feuerbach, Karl Marx lalu mengubah Dialektika Ide menjadi Dialektika Materialisme, sebuah proses kemajuan dari kontradiksi-kontradiksi tesis – antitesis – sintesis, yang sudah diujudkan dalam dunia materi. Dialektika Materialisme lalu digunakan sebagai alat interpretasi terhadap sejarah manusia dan perkembangannya. Interpretasi inilah yang disebut sebagai Historis Materialisme, yang menjadi dasar lahirnya ideologi SosialismeKomunisme (Marxisme) di Eropa Timur. Pada gilirannya, Pragmatisme dianggap juga salah satu aliran yang berpangkal pada Empirisme, kendatipun ada pula pengaruh Idealisme Jerman (Hegel) pada John Dewey, seorang tokoh Pragmatis¬me yang dianggap pemikir paling berpengaruh pada zamannya. Selain John Dewey, tokoh Pragmatisme lainnya adalah Charles Pierce dan William James. Konsep Maqashid al-Syari’ah al-Syatibi Musthafa Said al-Khin dalam bukunya al-Kafi al-Wafi fi Ushul alFiqh al-Islamy membuat sebuah terobosan baru mengenai kecenderungan aliran dalam Ilmu Ushul Fiqh. Bila sebelumnya hanya dikenal dua aliran saja, yaitu Mutakallimin dan fuqaha atau Syafi’iyyah dan Hanafiyyah, alKhin membaginya menjadi lima bagian: Mutakallimin, Hanafiyyah, alJam’i, Takhrij al-Furu’ ‘alal Ushul dan Syathibiyyah. Musthafa Said alKhin dalam bukunya al-Kafi al-Wafi fi Ushul al-Fiqh al-Islamy membuat sebuah terobosan baru mengenai kecenderungan aliran dalam Ilmu Ushul Fiqh. Bila sebelumnya hanya dikenal dua aliran saja, yaitu Mutakallimin dan fuqaha atau Syafi’iyyah dan Hanafiyyah, al-Khin membaginya menjadi lima bagian: Mutakallimin, Hanafiyyah, al-Jam’i, Takhrij al-Furu’ ‘alal Ushul dan Syathibiyyah. Pembagian ini, merupakan pembagian terbaru di mana thariqah yang ditempuh Imam Syathibi dalam al-Muwafaqat menjadi salah satu bagian corak aliran yang terpisah dari aliran ushul lainnya. Tidak 9 berlebihan memang, karena dalam coraknya al-Syathibi mencoba menggabungkan teori-teori (nadhariyyat) Ushul Fiqh dengan konsep Maqashid al-Syari’ah sehingga produk hukum yang dihasilkan lebih hidup dan lebih kontekstual. Ada dua nilai penting, hemat penulis, apabila model al-Syathibi ini dikembangkan para ulama sekarang dalam menggali hukum: Pertama, dapat menjembatani antara “aliran kanan” dan “aliran kiri”. “Aliran kanan” yang dimaksud adalah mereka yang tetap teguh berpegang pada konsep-konsep Ilmu Ushul Fiqh sedangkan “aliran kiri” adalah mereka yang terakhir ini vokal dengan idenya tajdid Ushul al-Fiqh dalam pengertian perlu adanya dekonstruksi Ushul Fiqh demi menghasilkan produk fiqh yang lebih kapabel. Di antara yang paling vokal menyuarakan konsep ini adalah Hasan al-Turaby dengan bukunya Tajdid Ushul al-Fiqh—buku ini dinyatakan terlarang dipasarkan. Meski sesungguhnya penulis kurang sependapat dengan tayyar alyasar ini, namun ada hal yang perlu dicatat bahwa apa yang mereka lontarkan adalah karena ketidakpuasannya dengan produk-produk fiqh para ulama yang terlalu terpaku pada teks tanpa mengindahkan konteks. Dengan demikian, produk hukum yang dihasilkan pun menjadi mati, ambigu, bahkan terkadang, menurut mereka, kurang manusiawi.[2] Keambiguan ini disebabkan methodologi yang ditempuh terlalu ushuli kurang memperhatikan Maqashid al-Syari’ah. Bisa jadi ulama-ulama Ushul dahulu telah membahas Maqashid alSyari’ah ini menjadi salah satu bagian dari ilmu Ushul. Hanya saja, perlu dicatat, pembahasan al-mutaqaddimin dengan Maqashid al-Syari’ah ini boleh dikatakan hanya sebagai “lipstik” saja karena pembahasannya yang begitu singkat dan cenderung kurang mewakili. Dengan corak metodologi Imam Syathibi dalam al-Muwafaqat-nya yang mencoba menggabungkan antara teori-teori Ushul dengan Maqashid al-Syari’ah akan menjadi penghubung sekaligus jembatan untuk meng“ishlahkan” kedua kecenderungan di atas. Memisahkan teori-teori Ushul Fiqh dengan Maqashid al-Syari’ah merupakan kesalahan besar karena tidak semua al-hawadits al-haditsah atau al-qaadimah dapat diselesaikan dengan Maqashid al-Syari’ah an.sich, meskipun Thahir bin Asyur dalam bukunya Maqashid al-Syari’ah al-Islamiyyah secara yakin menjadikan Maqashid al-Syari’ah ini sebagai ilmu mustaqil yang terlepas dari ilmu Ushul Fiqh.[3] Namun, dalam pandangan penulis, sesungguhnya teoriteori dan kerangka yang dikemukakan Thahir bin Asyur sendiri, disadari 10 atau tidak, adalah teori-teori Ushul Fiqh itu sendiri hanya dengan format yang berbeda. Kedua, model al-Syathibi ini akan lebih menghasilkan produk hukum yang dalam istilah Ibnu Qayyim, al fiqh al-hayy, fiqh yang hidup. Karena itu, fiqh yang terlalu teksbook yang penulis istilahkan dengan Fiqh Ushuly akan berubah menjadi Fiqh Maqashidy. Sedikit penulis mengajak para pembaca untuk bernostalgia ke Indonesia. Dalam pengamatan penulis, ada kesalahan fatal sikap masyarakat Indonesia khususnya terhadap fiqh. Ia lebih dipahami sebagai ilmu yang membahas tentang ritual dan tata cara ibadah an sich, yang terlepas dari nilai-nilai rububiyyah murni dan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini terlihat misalnya, mereka lebih asyik dengan menempelkan dahi di atas sajadah daripada memperhatikan tetangganya yang bergelut melawan penyakit yang menggerogoti tubuhnya yang kurus kering kurang gizi. Mereka lebih merasa berdosa tidak berdzikir setelah shalat atau makan daging anjing dari pada berbohong, menipu dan korupsi. Paling tidak, kesalahan ini adalah karena fiqh dipahami hanya ibadah yang kaitannya antara manusia dan Tuhan saja. Ada semacam pembatasan pemahaman fiqh di kalangan masyarakat dewasa ini sehingga lebih mementingakn menghapal syarat sah, syarat wajib, rukun dan lainnya dari pada efek ibadah itu sendiri. Padahal pada awalnya fiqh mencakup pula persoalan tauhid dan akhlak seperti yang terdapat dalam Kitab al-Fiqh al-Akbar karya Imam Abu Hanifah atau Ihya Ulumiddin karya Imam Ghazali. Di samping itu, silabus pengajaran fiqh di Indonesia, sepengetahuan penulis, juga kurang mengarah pada Fiqh Maqashidy. Hampir tidak ada, hemat penulis, silabus yang khusus membahas tentang Maqashid al-Syari’ah. Karenanya, tidaklah heran ekses fiqh tidak berpengaruh pada tataran amaliyyah yaumiyyah, ia lebih pada tataran fardhiyyah syakhsiyyah. Akhirnya, shalat dan ibadah rajin, korupsi jalan terus. Inilah gambaran bagaiman fiqh itu mati, ambigu, sangat ushuly tidak hidup dan tidak maqashidy. Dari paparan di atas jelas, kebutuhan untuk memahami dan mengkampanyekan Maqashid al-Syari’ah di samping Ushul Fiqh menjadi sangat penting adanya. Demi menuju ke arah itu, penulis merasa terpanggil untuk mengungkap sekilas perjalanan Imam Sythibi sebagai Bapak Maqashid al-Syari’ah Pertama sekaligus sekilas tentang Maqashid al-Syari’ah versi Syathibi. 11 Imam Syathibi membahas tentang Maqashid al-Syari’ah ini dalam kitabnya al-Muwafaqat juz II sebanyak 313 halaman (menurut buku cetakan Dar al-Kutub al-Ilmiyyah). Persoalan yang dikemukakan di dalamnya sebanyak 62 masalah. Dalam pembahasannya, Imam Syathibi membagi al-Maqashid ini kepada dua bagian penting yakni Maksud Syari’ (qashdu al-syari’) dan Maksud Mukallaf (qashdu al-mukallaf). Maksud Syari’ kemudian dibagi lagi menjadi 4 bagian yaitu: 1. Qashdu al-Syari’ fi Wadh’i al-Syari’ah (Maksud Syari’ dalam Menetapakan Syari’at) Dalam bagian ini ada 13 permasalahan yang dikemukakan. Namun semuanya mengacu kepada suatu pertanyaan: “Apakah sesungguhnya maksud syari dengan menetapkan syari’atnya itu?” Menurut Imam Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (jalbul mashalih wa dar’ul mafasid). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturanaturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Syathibi kemudian membagi maslahat ini kepada tiga bagian penting yaitu dharuriyyat (primer), hajiyyat (skunder) dan tahsiniyat (tersier,lux). Maqashid atau Maslahat Dharuriyyat adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan[39] seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya. Yang termasuk maslahat atau maqashid dharuriyyat ini ada lima yaitu: agama (al-din), jiwa (al-nafs), keturunan (an-nasl), harta (al-mal) dan aqal (al-aql).[40] Cara untuk menjaga yang lima tadi dapat ditempuh dengan dua cara yaitu: Pertama, Dari segi adanya (min nahiyyati al-wujud) yaitu dengan cara manjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya; Kedua, Dari segi tidak ada (min nahiyyati al- ‘adam) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini: a. Menjaga agama dari segi al-wujud misalnya shalat dan zakat b. Menjaga agama dari segi al-‘adam misalnya jihad dan hukuman bagi orang murtad c. Menjaga jiwa dari segi al-wujud misalnya makan dan minum d. Menjaga jiwa dari segi al-‘adam misalnya hukuman qishash dan diyat e. Menjaga aqal dari segi al-wujud misalnya makan dan mencari ilmu 12 f. Menjaga aqal dari segi al-‘adam misalnya had bagi peminum khamr g. Menjaga an-nasl dari segi al-wujud misalnya nikah h. Menjaga an-nasl dari segi al-‘adam misalnya had bagi pezina dan muqdzif i. Menjaga al-mal dari segi al-wujud misalnya jual beli dan mencari rizki j. Menjaga al-mal dari segi al-‘adam misalnya riba, memotong tangan pencuri. Sebelum penulis memaparkan lebih jauh cara kerja dan aflikasi dari al-dharuriyyat al-khams ini, perlu penulis sampaikan terlebih dahulu urutan kelima dharuriyyat ini baik menurut Imam Syathibi maupun ulama ushul lainnya. Hal ini sangat penting karena berpengaruh pada kesimpulan hukum yang akan dihasilkan. Urutan kelima dharuriyyat ini bersifat ijtihady bukan naqly, artinya ia disusun berdasarkan pemahaman para ulama terhadap nash yang diambil dengan cara istiqra. Dalam merangkai kelima dharuriyyat ini (ada juga yang menyebutnya dengan al-kulliyyat alkhamsah), Imam Syathibi terkadang lebih mendahulukan aql dari pada nasl, terkadang nasl terlebih dahulu kemudian aql dan terkadang nasl lalu mal dan terakhir aql. Namun satu hal yang perlu dicatat bahwa dalam susunan yang manapun Imam Syathibi tetap selalu mengawalinya dengan din dan nafs terlebih dahulu. Dalam al-Muwafaqat I/38, II/10, III/10 dan IV/27 urutannya adalah sebagai berikut: ad-din (agama), an-nafs (jiwa), an-nasl (keturunan), al-mal (harta) dan al-aql (akal). Sedangkan dalam al-Muwafaqat III/47: ad-din, annafs, al-aql, an-nasl dan al-mal. Dan dalam al-I’tisham II/179 dan alMuwafaqat II/299: ad-din, an-nafs, an-nasl, al-aql dan al-mal. Perbedaan urutan di atas, menunjukkan bahwa semuanya sah-sah saja karena sifatnya ijtihadi. Para ulama ushul lainnya pun tidak pernah ada kata sepakat tentang hal ini. Bagi al-Zarkasyi misalnya, urutan itu adalah:[41] an-nafs, al-mal, an-nasab, ad-din dan al-‘aql. Sedangkan menurut al-Amidi:[42] ad-din, an-nafs, an-nasl, al-aql dan al-mal. Bagi al-Qarafi:[43] an-nufus, al-adyan, al-ansab, al-‘uqul, al-amwal atau al-a’radh. Sementara menurut al-Ghazali:[44] ad-din, an-nafs, al-‘aql, an-nasl dan al-mal. Namun urutan yang dikemukakan al-Ghazali ini adalah urutan yang paling banyak dipegang para ulama Fiqh dan Ushul Fiqh berikutnya. Bahkan, Abdullah Darraz, pentahkik al-Muwafaqat sendiri, memandang urutan versi al-Ghazali ini adalah yang lebih mendekati kebenaran.[45] Cara kerja dari kelima dharuriyyat di atas adalah masingmasing harus berjalan sesuai dengan urutannya. Menjaga al-din harus lebih didahulukan daripada menjaga yang lainnya; menjaga al-nafs harus 13 lebih didahulukan dari pada al-aql dan nasl begitu seterusnya. Salah satu contoh yang dapat penulis kemukakan adalah membunuh diri atau menceburkan diri dalam kebinasaan adalah sesuatu yang dilarang sebagaimana bunyi teks dalam surat al-Baqarah. Akan tetapi kalau untuk kepentingan berjihad dan kepentingan agama Allah, menjadi boleh karena sebagaimana telah disinggung diatas bahwa menjaga agama harus didahulukan dari pada menjaga jiwa. Oleh kerena itu, sebagian besar para ulama membolehkan istisyhad para pejuang Palestina dengan pertimbangan hukum di atas. Akan tetapi bagaimana dengan kasus orang sakit yang kerena suatu kebutuhan pengobatan boleh dilihat auratnya atau musafir yang boleh mengqashar shalat, bukankah itu berarti an-nafs lebih didahulukan dari pada ad-din? Persoalan ini sesungguhnya bukanlah persoalan baru. Al-Amidy dalam al-Ahkam-nya, misalnya, telah mengulas secara panjang lebar yang tidak mungkin penulis kutipkan di sini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat langsung dalam al-Ahkam fi Ushul al-Ahkam (sebagian membacanya al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, akan tetapi penulis lebih condong membacanya al-Ahkam) juz IV halaman 243-245. Dalam kesempatan ini penulis hanya akan mengutip pendapat Abdullah Darraz karena lebih ringkas. Menurutnya bahwa dalam tataran umum agama harus lebih didahulukan daripada yang lainnya karena ini menyangkut ushul al-din, sedangakan dalam hal tertentu jiwa dan harta terkadang lebih didahulukan dari pada agama (mustatsnayyat). Disinilah dibutuhkan kejelian seorang mujtahid.[46] Maqashid atau Maslahah Hajiyyat adalah sesuatu yang sebaiknya ada agar dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian hanya saja akan mengakibatkan masyaqah dan kesempitan.[47] Misalnya, dalam masalah ibadah adalah adanya rukhsah; shalat jama dan qashar bagi musafir. Maqashid atau Maslahah Tahsinat adalah sesuatu yang sebaiknya ada demi sesuainya dengan keharusan akhlak yang baik atau dengan adat. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka tidak akan menimbulkan kerusakan atau hilangnya sesuatu juga tidak akan menimbulkan masyaqah dalam melaksanakannya, hanya saja dinilai tidak pantas dan tidak layak manurut ukuran tatakrama dan kesopanan. Di antara contohnya adalah thaharah, menutup aurat dan hilangnya najis. Ada beberapa qaidah penting yang dikemukakan Imam Syathibi dalam menerangkan keterkaitan atau cara kerja ketiga maslahah di atas yang tidak mungkin penulis kemukakan di sini mengingat panjangnya 14 pembahasan dimaksud. Namun untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam masalah ke-4 halaman 13 buku al-Muwafaqat. 2. Qashdu al-Syari’ fi Wadh’I al-Syari’ah lil Ifham (Maksud Syari’ Dalam Menetapkan Syari’atnya Agar Dapat Difahami). Bagian ini merupakan pembahasan yang peling singkat karena hanya mencakup 5 masalah. Dalam menetapkan syari’atnya, Syari’ bertujuan agar mukallaf dapat memahaminya, itulah maksud dari bagian kedua. Ada dua hal penting yang dibahas dalam bagian ini. Pertama, syari’ah ini diturunkan dalam Bahasa Arab sebagaimana firmanNya dalam surat Yusuf ayat 2; as-Syu’ara:195. Oleh kerena itu, untuk dapat memahaminya harus terlebih dahulu memahami seluk beluk dan uslub bahasa Arab. Dalam hal ini Imam Syathibi berkata: “Siapa orang yang hendak memahaminya, maka dia seharusnya memahami dari sisi lidah Arab terlebih dahulu Karena tanpa ini tidak mungkin dapat memahaminya secara mantap. Inilah yang menjadi pokok dari pembahasan masalah ini”. Dengan bahasa lebih mudah, di samping mengetahui bahasa Arab, untuk memahami syari’at ini juga dibutuhkan ilmu-ilmu lain yang erat kaitannya dengan lisan Arab seperti Ushul Fiqh, Mantiq, Ilmu Ma’ani dan yang lainnya. Karenanya, tidaklah heran apabila bahasa Arab, Ushul Fiqh termasuk salah satu persyaratan pokok yang harus dimiliki seorang mujtahid. Kedua, bahwa syari’at ini ummiyyah, maksudnya untuk dapat memahaminya tidak membutuhkan bantuan ilmu-ilmu alam seperti ilmu hisab, kimia, fisika dan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar syari’ah mudah dipahami oleh semua kalangan manusia. Apabila untuk memahami syari’at ini memerlukan bantuan ilmu lain seperti ilmu alam, paling tidak ada dua kendala besar yang akan dihadapi manusia umumnya, yaitu kendala dalam hal pemahaman dan dalam pelaksanaan. Syari’ah mudah dipahami oleh siapa saja dan dari bidang ilmu apa saja karena ia berpangkal kepada konsep maslahah (fahuwa ajraa ‘ala i’tibari al-maslahah). Di antara landasan bahwa syari’at ini ummiyyah adalah karena pembawa syari’at itu sendiri (Rasulullah Saw) adalah seorang yang ummi sebagaimana ditegaskan dalam firmanNya surat al-Jum’ah ayat 2, al-Araf ayat 158, al-Ankabut 48 dan keterangan-keterangan lainnya. Ada kecenderungan berlebihan dari sebagian ulama yang tidak sesuai dengan sifat syari’ah ummiyyah ini, lanjut Syathibi, yaitu bahwa al-Qur’an mencakup semua bidang keilmuan, baik keilmuan lama ataupun modern. 15 Betul, lanjut Syathibi, al-Qur’an menyinggung dan sesuai dengan berbagai disiplin ilmu, namun tidak berarti al-Qur’an mencakup semuanya, itu semua hanyalah isyarat saja dan bukan sebagai legitimasi semua disiplin ilmu. Ayat yang sering dijadikan dalil adalah surat an-Nahl 89 yang berbunyi: “Dan Kami turunkan kepadamu al-Qur’an untuk menjelaskan segala sesuatu”, dn surat al-An’am ayat 38 yang berbunyi: “Tidaklah Kami lewatkan sesuatupun dari al-Qur’an”. Menurut Syathibi, kedua ayat di atas mempunyai makna tertentu. Ayat pertama dimaksudkan mengenai masalah taklif dan ibadah sedangkan maksud al-kitab dalam ayat kedua adalah allauh al-mahfudz. 3. Qashdu al-Syari’ fi Wadh’I al-Syari’ah li al-Taklif bi Muqtadhaha Bagian ini dimaksudkan bahwa maksud Syari’ dalam menentukan syari’at adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan yang dituntutNya. Masalah yang dibahas dalam bagian ini ada 12 masalah, namun semuanya mengacu kepada dua masalah pokok yaitu: Pertama, taklif yang di luar kemampuan manusia (at-taklif bima laa yuthaq).Pembahasan ini tidak akan dibahas lebih jauh karena sebagaimana telah diketahui bersama bahwa tidaklah dianggap taklif apabila berada di luar batas kemampuan manusia. Dalam hal ini Imam Syathibi mengatakan: “Setiap taklif yang di luar batas kemampuan manusia, maka secara Syar’i taklif itu tidak sah meskipun akal membolehkannya”.[54] Apabila dakan teks Syari’ ada redaksi yang mengisyaratkan perbuatan di luar kemampuan manusia, maka harus dilihat pada konteks, unsur-unsur lain atau redaksi sebelumnya. Misalnya, furman Allah: “Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim”. Ayat ini bukan berarti larangan untuk mati karena mencegah kematian adalah di luar batas kemampuan manusia. Maksud larangan ini adalah larangan untuk memisahkan antara keislalman dengan kehidupan di dunia ini karena datangnya kematian tidak akan ada yang mengetahui seorangpun. Begitu juga dengan sabda Nabi: “Janganlah kamu marah” tidak berarti melarang marah, karena marah adalah tabiat manusia yang tidak mungkin dapat dihindari. Akan tetapi maksudnya adalah agar sedapat mungkin menahan diri ketika marah atau menghindari hal-hal yang mengakibatkan marah. Kedua, taklif yang di dalamnya terdapat masyaqah, kesulitan (al-taklif bima fiihi masyaqqah). Persoalan inilah yang kemudian dibahas panjang lebar oleh Imam Syathibi. Menurut Imam Syathibi, dengan adanya taklif, 16 Syari’ tidak bermaksud menimbulkan masyaqah bagi pelakunya (mukallaf) akan tetapi sebaliknya di balik itu ada manfaat tersendiri bagi mukalla. Bila dianalogkan kepada kehidupan sehari-hari, obat pahit yang diberikan seorang dokter kepada pasien, bukan berarti memberikan kesulitan baru bagi sang pasien akan tetapi di balik itu demi kesehatan si pasien itu sendiri pada masa berikutnya. Dalam masalah agama misalnya, ketika ada kewajiban jihad, maka sesungguhnya tidak dimaksudkan dengannya untuk menceburkan diri dalam kebinasaan, tetapi untuk kemaslahatan manusia itu sendiri yaitu sebagai wasilah amar makruf nahyil munkar. Demikian pula dengan hukum potong tangan bagi pencuri, tidak dimaksudkan untuk merusak anggota badan akan tetapi demi terpeliharanya harta orang lain. Apabila dalam taklif ini ada masyaqah, maka sesungguhnya ia bukanlah masyaqah tapi kulfah, sesuatu yang tidak mungkin dapat dipisahkan dari kegiatan manusia sebagaimana dalam kacamata adat, orang yang memikul barang atau bekerja siang malam untuk mencari kehidupan tidak dipandang sebagai masyaqah, tetapi sebagai salah satu keharusan dan kelaziman untuk mencari nafkah. Demikian juga halnya dengan masalah ibadah. Masyaqah seperti ini menurut Imam Syathibi disebut Masyaqah Mu’tadah karena dapat diterima dan dilaksanakan oleh anggota badan dan karenanya dalam syara’ tidak dipandang sebagai masyaqah. Yang dipandang sebagai masyaqah adalah apa yang disebutnya dengan Masyaqah Ghair Mu’tadah atau Ghair ‘Adiyyah yaitu masaqah yang tidak lazim dan tidak dapat dilaksanakan atau apabila dilaksanakan akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Misalnya, keharusan berpuasa bagi orang sakit dan orang jompo. Semua ini adalah masyaqah ghair mu’tadah yang dikecam oleh Islam. Untuk mengatasi masyaqah ini, Islam memberikan jalan keluar melalui rukhshah atau keringanan. 4. Qashdu al-Syari’ fi Dukhul al-Mukallaf Tahta Ahkam al-Syari’ah Pembahasan bagian terakhir ini merupakan pembahasan paling panjang mencakup 20 masalah. Namun semuanya mengacu kepada pertanyaan: “Mengapa mukallaf melaksanakan hukum Syari’ah?” Jawabannya adalah untuk mengeluarkan mukallaf dari tuntutan dan keinginan hawa nafsunya sehingga ia menjadi seorang hamba yang dalam istilah Imam Syathibi disebut: hamba Allah yang ikhtiyaran dan bukan yang idthiraran. Atau dalam istilah Dr. Ahmad Zaid: Ikhrajul ‘abd min da’iyatil hawa ila dairatil ‘ubudiyyah. 17 Untuk itu, setiap perbuatan yang mengikuti hawa nafsu, maka ia batal dan tidak ada manfa’atnya. Sebaliknya, setiap perbuatan harus senantiasa mengikuti petunjuk Syari’ dan bukan mengikuti hawa nafsu. Ada beberapa kaidah penting yang perlu dipahami dalam bagian ini dan penulis tidak dapat menjelaskannya dalam bahasa Indonesia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam al-Muwafaqat Juz II hal. 128-150. Demikian sekilas tentang Maqashid al-Syari’ah menurut Imam Syathibi. Gambaran di atas tentunya tidak memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang Maqashid Syari’ah itu sendiri, namun paling tidak tergambar bahwa rumusan Imam Syathibi ini lebih sistematis dan lengkap dibandingkan rumusan-rumusan para ulama Ushul sebelumnya. Apa yang tertulis dalam al-Muwafaqat khususnya dan karya-karta Imam Syathibi lainnya betul-betul telah mempengaruhi pemikiran para ulama berikutnya semisal Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha, Abdullah Darraj, Muhammad Thahir bin Asyur dan ‘Allal Fasy. Muhammad Abduh adalah orang pertama yang mengumumkan pentingnya ulama-ulama dan para mahasiswa Timur Tengah untuk mempelajari karya-karya Imam Syathibi terutama al-Muwafaqat. Sama halnya dengan muridnya, Rasyid Ridha. Bahkan bukan saja terpengaruh dengan ide maqashidnya Imam Syathibi, ia juga sangat terpengaruh dengan al-I’tishamnya demi menghidupkan kembali harakah salafiyyah yang sejak lama diusungnya. Demikian juga dengan Thahir bin Asyur. Ulama asal Tunis ini telah mengarang sebuah buku berjudul Maqashid al-Syari’ah al-Islamiyyah yang sempat menggegerkan ulama Ushul Timur Tengah karena idenya yang mencoba mengenyampingkan Ushul Fiqh dan menggantinya dengan Maqashid al-Syari’ah. Baginya, Maqashid al-Syari’ah merupakan ilmu yang berdiri sendiri (‘ilm mustaqil) dan terlepas dari Ilmu Ushul bahkan Ilmu Ushul dipandangnya sebagai ilmu yang telah usang dan produk fiqhnya cenderung kurang manusiawi. Namun demikian, idenya lahir karena pengaruh dari Imam Syathibi, bahkan Abdul Majid Turki memandang buku Thahir bin Asyur ini sebagai mustalhaman min kitab alMuwafaqat (jiplakan dari kitab al-Muwafaqat). Allal Fasy, ulama asal Maroko, juga termasuk meraka yang terpengaruh oleh ide Syathibi. Bukunya Difa’ ‘an al-Syari’ah dan Maqashid al-Syari’ah al-Islamiyyah wa Makarimuha merupakan perluasan dan terkadang pengulangan dari apa yang tertulis dalam al-Muwafaqat. Karena besarnya pengaruh Syathibi dengan al-Muwafaqatnya inilah, ulama-ulama Ushul kemudian sepakat menjadikan Imam Syathibi sebagai 18 Bapak Maqashid al-Syari’ah pertama yang telah menyusun teori-teorinya secara lengkap, sistematis dan jelas. Sebagai ilustrasi dapat disebutkan di sini empat teori hukum terbaru di abad ke-20 yang dapat diketahui orang untuk mempelajari hukum Barat, antara lain: (1) teori pemakaian hak semena-mena (Isa’atu isti’malil hak); (2) teori keadaan mendadak (ad-Dhurufat thari’ah); (3) teori pertanggungan kekuasaan (Massalijatu Adami at-Tamyiz). Namun formulasi keempat teori hukum tersebut, sebenarnya telah banyak disinggung dalam prinsip-prinsip dasar pembinaan hukum Islam sejak masa awal pertumbuhannya. Pada gilirannya, dalam sebuah seminar hukum di Den Haag Belanda tahun 1937, Syeikh Machmoud Syalthouth (Rektor Universitas Al-Azhar) dan Dr. Hasan Sufi Abu Thalib menegaskan bahwa: Pertama, hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum umum; Kedua, hukum Islam merupakan hukum yang hidup dan berkembang; dan ketiga, hukum Islam merupakan hukum yang berdiri sendiri dan tidak diambil dari hukum lain.1 Pengaruh Positivisme Dalam Pemikiran Hukum Islam Kekeliruan Pragmatisme dapat dibuktikan dalam tiga tataran pemikiran : 1. Kritik dari Segi Landasan Ideologi Pragmatisme dilandaskan pada pemikiran dasar (Aqidah) pemisahan agama dari kehi¬dupan (sekularisme). Hal ini nampak dari perkembangan historis kemunculan Pragmatisme, yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari Empirisme. Dengan demikian, dalam konteks ideologis, Pragmatisme berarti menolak agama sebagai sumber ilmu pengetahuan. Aqidah pemisahan agama dari kehidupan adalah landasan ideologi Kapitalisme. Aqidah ini, sebenarnya bukanlah hasil proses berpikir. Bahkan, tak dapat dikatakan sebagai pemikiran yang logis. Aqidah pemisahan agama dari kehidupan tak lain hanyalah penyelesaian yang berkecenderungan ke arah jalan tengah atau bersikap moderat, antara dua pemikiran yang kontradiktif. Kedua pemikiran ini, yang pertama adalah 1 A. Hanafi membuka penilaian atas penelitian hukum Islam sesungguhnya merupakan hukum yang berlaku umum, tidak terbatas dalam wilayah geografis suatu negara, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan hidup modern, sebagaimana ia telah membuktikannya dari hasil Seminar Hukum di Den Haag pada bulan Agustus 1948 dan Seminar Hukum di Paris Perancis bulan Juli 1951. Lihat Ibid., hlm. 202-203. 19 pemikiran yang diserukan oleh tokoh-tokoh gereja di Eropa sepanjang Abad Pertengahan (abad V - XV M), yakni keharusan menun¬dukkan segala sesuatu urusan dalam kehidupan menurut ketentuan agama. Sedangkan yang kedua, adalah pemikiran sebagian pemikir dan filsuf yang mengingkari keberadaan Al Khaliq. Jadi, pemikiran pemisahan agama dari kehidupan merupakan jalan tengah di antara dua sisi pemikiran tadi. Penyelesaian jalan tengah, sebenarnya mungkin saja terwujud di antara dua pemikiran yang berbeda (tapi masih mempunyai asas yang sama). Namun penyelesaian seperti itu tak mungkin terwujud di antara dua pemikiran yang kontradiktif. Sebab dalam hal ini hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, ialah mengakui keberadaan Al Khaliq yang menciptakan manusia, alam semesta, dan kehidupan. Dan dari sinilah dibahas, apakah Al Khaliq telah menentukan suatu peraturan tertentu lalu manusia diwajibkan untuk melaksanakannya dalam kehidupan, dan apakah Al Khaliq akan menghisab manusia setelah mati mengenai keterika¬tannya terhadap peraturan Al Khaliq ini. Sedang yang kedua, ialah mengingkari keberadaan Al Khaliq. Dan dari sinilah dapat dicapai suatu kesimpulan, bahwa agama tidak perlu lagi dipisahkan dari kehidupan, tapi bahkan harus dibuang dari kehidupan. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa keberadaan Al Khaliq tidaklah lebih penting daripada ketiadaan-Nya, maka ini adalah suatu ide yang tidak memuaskan akal dan tidak menenteramkan jiwa. Jadi, berdasarkan fakta bahwa aqidah Kapitalisme adalah jalan tengah di antara pemi¬kiran-pemikiran kontradiktif yang mustahil diselesaikan dengan jalan tengah, maka sudah cukuplah bagi kita untuk mengkritik dan membatalkan aqidah ini. Tak ada bedanya apakah aqidah ini dianut oleh orang yang mempercayai keberadaan Al Khaliq atau yang mengingkari keberadaan-Nya. Tetapi dalam hal ini dalil aqli (dalil yang berlandaskan keputusan akal) yang qath’i (yang bersifat pasti), membuktikan bahwa Al Khaliq itu ada dan Dialah yang menciptakan manusia, alam semesta, dan kehidupan. Dalil tersebut juga membuktikan bahwa Al Khaliq ini telah menetapkan suatu peraturan bagi manusia dalam kehidupannya, dan bahwasanya Dia akan menghisab manusia setelah mati mengenai keterikatannya terhadap peraturan Al Khaliq tadi. Kendatipun demikian, di sini bukan tempatnya untuk melakukan pembahasan tentang eksistensi Al Khaliq atau pembahasan mengenai peraturan yang ditetapkan Al Khaliq untuk manusia. Namun yang 20 menjadi fokus pembahasan di sini ialah aqidah Kapitalisme itu sendiri dan penjelasan mengenai kebatilannya. Dan kebatilan Kapitalisme cukup dibuktikan dengan menunjukkan bahwa aqidah Kapitalisme tersebut merupakan jalan tengah antara dua pemikiran yang kontradiktif, dan bahwa aqidah tersebut tidak dibangun atas dasar pembahasan akal. Kritik yang merobohkan aqidah Kapitalisme ini, sesungguhnya sudah cukup untuk merobohkan ideologi Kapitalisme secara keseluruhan. Sebab, seluruh pemikiran cabang yang dibangun di atas landasan yang batil –termasuk dalam hal ini Pragmatisme– pada hakekatnya adalah batil juga. 2. Kritik dari Segi Metode Berpikir Pragmatisme yang tercabang dari Empirisme nampak jelas menggunakan Metode Ilmiah (Ath Thariq Al Ilmiyah), yang dijadikan sebagai asas berpikir untuk segala bidang pemikiran, baik yang berkenaan dengan sains dan teknologi maupun ilmu-ilmu sosial. Ini adalah suatu kekeliruan. Metode Ilmiah adalah suatu metode tertentu untuk melakukan pembahasan/pengkajian untuk mencapai kesimpulan pengertian mengenai hakekat materi yang dikaji, melalui serang¬kaian percobaan/eksperimen yang dilakukan terhadap materi. Metode ini merupakan metode yang benar untuk objek-objek yang bersifat materi/fisik seperti halnya dalam sains dan teknologi. Tetapi menjadikan Metode Ilmiah sebagai landasan berpikir untuk segala sesuatu pemikiran adalah suatu kekeliruan, sebab yang seharusnya menjadi landasan pemikiran adalah Metode Akliyah/Rasional (Ath Thariq Al Aqliyah), bukan Metode Ilmiah. Sebab, Metode Ilmiah itu sesungguhnya hanyalah cabang dari Metode Aqliyah. Metode Aqliyah adalah sebuah metode berpikir yang terjadi dalam proses pemahaman sesuatu sebagaimana definisi akal itu sendiri, yaitu proses transfer realitas melalui indera ke dalam otak, yang kemudian diinterpretasikan dengan sejumlah informasi sebelumnya yang bermukim dalam otak. Metode Aqliyah ini sesungguhnya merupakan asas bagi kelahiran Metode Ilmiah, atau dengan kata lain Metode Ilmiah sesungguhnya tercabang dari Metode Aqliyah. Argumen untuk ini, sebagaimana disebutkan Taqiyuddin An-Nabhani dalam At Tafkir halaman 32-33, ada dua point : a. Bahwa untuk melaksanakan eksperimen dalam Metode Ilmiah, tak dapat tidak pasti dibutuhkan informasi-informasi sebelumnya. Dan 21 informasi sebelumnya ini, diperoleh melalui Metode Akliyah, bukan Metode Ilmiah. Maka, Metode Akliyah berarti menjadi dasar bagi adanya Metode Ilmiah. b. Bahwa Metode Ilmiah hanya dapat mengkaji objek-objek yang bersifat fisik/materi¬al yang dapat diindera. Dia tak dapat digunakan untuk mengkaji objek-objek pemikiran yang tak terindera seperti sejarah, bahasa, logika, dan hal-hal yang ghaib. Sedang Metode Akliyah, dapat mengkaji baik objek material maupun objek pemikiran. Maka dari itu, Metode Akliyah lebih tepat dijadikan asas berpikir, sebab jangkauannya lebih luas daripada Metode Ilmiah. Atas dasar dua argumen ini, maka Metode Ilmiah adalah cabang dari Metode Akliyah. Jadi yang menjadi landasan bagi seluruh proses berpikir adalah Metode Akliyah, bukan Metode Ilmiah, sebagaimana yang terdapat dalam Pragmatisme. 3. Kritik Terhadap Pragmatisme Itu Sendiri Pragmatisme adalah aliran yang mengukur kebenaran suatu ide dengan kegunaan prak¬tis yang dihasilkannya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ide ini keliru dari tiga sisi: Pertama, Pragmatisme mencampur adukkan kriteria kebenaran ide dengan kegunaan praktisn¬ya. Kebenaran suatu ide adalah satu hal, sedang kegunaan praktis ide itu adalah hal lain. Kebenaran sebuah ide diukur dengan kesesuaian ide itu dengan realitas, atau dengan standarstandar yang dibangun di atas ide dasar yang sudah diketahui kesesuaiannya dengan realitas. Sedang kegunaan praktis suatu ide untuk memenuhi hajat manusia, tidak diukur dari keberhasilan penerapan ide itu sendiri, tetapi dari kebenaran ide yang diterapkan. Maka, kegunaan praktis ide tidak mengandung implikasi kebenaran ide, tetapi hanya menunjukkan fakta terpuaskannya kebutuhan manusia. Kedua, Pragmatisme menafikan peran akal manusia. Menetapkan kebenaran sebuah ide adalah aktivitas intelektual dengan menggunakan standar-standar tertentu. Sedang penetapan kepuasan manusia dalam pemenuhan kebutuhannya adalah sebuah identifika¬si instinktif. Memang identifikasi instinktif dapat menjadi ukuran kepuasan manusia dalam pemuasan hajatnya, tapi tak dapat menjadi ukuran kebenaran sebuah ide. Maka, Pragmatisme berarti telah menafikan aktivitas intelektual dan menggantinya dengan identifikasi instinktif. Atau dengan kata lain, Pragmatisme telah menundukkan keputusan akal kepada kesimpulan yang dihasilkan dari identifikasi instinktif. 22 Ketiga, Pragmatisme menimbulkan relativitas dan kenisbian kebenaran sesuai dengan perubahan subjek penilai ide –baik individu, kelompok, dan masyarakat– dan perubahan konteks waktu dan tempat. Dengan kata lain, kebenaran hakiki Pragmatisme baru dapat dibuktikan – menurut Pragmatisme itu sendiri– setelah melalui pengu¬jian kepada seluruh manusia dalam seluruh waktu dan tempat. Dan ini mustahil dan tak akan pernah terjadi. Maka, Pragmatisme berarti telah menjelaskan inkonsistensi internal yang dikandungnya dan menafikan dirinya sendiri. 4. Kontradiksi Pragmatisme Dengan Islam Jelas sekali bahwa Pragmatisme –sebagai standar ide dan perbuatan– sangat bertentan¬gan dengan Islam. Sebab Islam memandang bahwa standar perbuatan adalah halal haram, yaitu perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Bukan kemanfaatan atau kegunaan riil untuk memenuhi kebutuhan manusia yang dihasilkan oleh sebuah ide, ajaran, teori, atau hipotesis. Allah SWT berfirman: “Berilah keputusan di antara mereka dengan apa yang diturunkan Allah” (Al Maaidah : 48). Syaikh An Nabhani menjelaskan ayat ini dalam Muqaddimah Dustur, bahwa ukuran perbuatan adalah apa yang diturunkan oleh Allah, bukan konsekuensikonsekuesi yang dihasilkan dari aktivitas-aktivitas manusia. Selain itu, Allah SWT telah memerintahkan untuk mengikuti apa yang diturunkan-Nya, yaitu Syari’at Islam. Allah SWT berfirman: “Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu mengikuti wali (pemimpin/sahabat/sekutu) selainnya…” (Al A’raaf :3) Mafhum Mukhalafah (pengertian kebalikan) dari ayat di atas adalah, janganlah kita mengikuti apa yang tidak diturunkan Allah, termasuk manfaat-manfaat atau kegunaan-kegunaan yang muncul sebagai konsekuensi dari aktivitas kita, sebab semuanya bukan termasuk apa yang diturunkan Allah. Allah SWT juga telah berfirman: “Apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu, maka ambillah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah dia…” (Al Hasyr : 7) Mafhum Mukhalafah ayat ini adalah, janganlah kita mengambil apa saja (pandangan hidup) yang tidak berasal dari Rasul, termasuk ide Pragmatisme. Ide ini tidak berasal dari Muhammad Rasulullah saw, tetapi dari orang-orang kafir yang berasal dari Eropa dan Ameri¬ka. Jelas, bahwa Pragmatisme bertentangan dengan Islam. Sebab ukuran perbuatan dalam Islam adalah perintah dan larangan Allah, bukan 23 manfaat riil suatu ide untuk memenuhi kebu¬tuhan manusia. Namun demikian, bukan berarti Islam tidak memperhatikan kemanfaatan. Islam terbukti telah memperhatikan aspek kemanfaatan, seperti misalnya sabda Rasulullah saw: “Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga perkara; shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak shaleh yang mendoakan kedua orang tuanya.” (HSR. Muslim) Benar, Islam memang memperhatikan kemanfaatan, tetapi kemanfaatan yang telah dibenarkan oleh syara’, bukan kemanfaatan secara mutlak tanpa distandarisasi lebih dulu oleh syara’. Hal ini karena nash-nash yang berhubungan dengan manfaat tidak dapat dipahami secara terpisah dari nash-nash lain yang menegaskan aspek halal haram. Maka, kemanfaatan yang diperhatikan oleh Islam adalah kemanfaatan yang dibenarkan oleh syara’, bukan sembar¬ang manfaat. Jadi, ketika dinyatakan bahwa standar perbuatan adalah syara’, dan bukan manfaat, maka hal ini tidak berarti bahwa Islam menafikan aspek kemanfaatan. Tetapi maknanya adalah, manfaat itu bukan standar kebenaran untuk ide atau perbuatan manusia. Sedang kemanfaatan yang dibenarkan Islam, yakni yang telah diukur dan ditakar dengan standar halal haram, maka itu adalah manfaat yang yang dapat diambil oleh manusia sesuai kehendaknya. Dekonstruksi Pragmatisme, Suatu Kewajiban. Pragmatisme adalah ide batil dan ide kufur yang sangat mungkar, karena ide tersebut dibangun di atas landasan ideologi yang kufur, dihasilkan dengan metode berpikir yang tidak tepat, serta mengandung kerancuan dan kekacauan pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, karena Pragmatisme adalah suatu kemungkaran, maka seorang muslim wajib menghancurkan dan membuang Pragmatisme dengan sekuat tenaga serta melawan siapa saja yang hendak menyesatkan umat dengan menjajakan ide hina dan berbahaya ini di tengah-tengah umat Islam yang sedang berjalan menuju kepada kebangkitannya. Sumber: Muhammad shiddiq al-jawi dalam http://ayok.wordpress.com/2006/12/20/dekonstruksi-pragmatisme/ 24