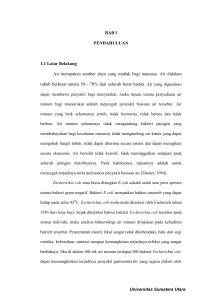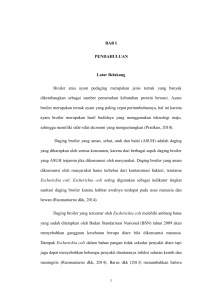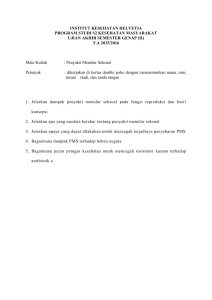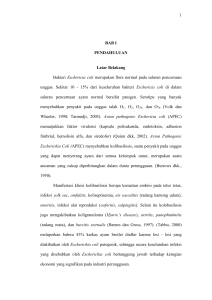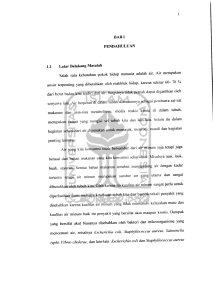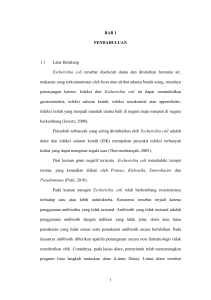7 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Ayam Pedaging (Ayam Broiler
advertisement

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Ayam Pedaging (Ayam Broiler) Ayam pedaging digolongkan kedalam kelompok unggas penghasil daging, artinya dipelihara khusus untuk menghasilkan daging. Umumnya memiliki ciriciri sebagai berikut: kerangka tubuh besar, pertumbuhan badan cepat, pertumbuhan bulu yang cepat, lebih efisien dalam mengubah ransum menjadi daging. Ayam pedaging adalah galur ayam hasil rekayasa genetik yang memiliki karakter ekonomis dengan ciri khas pertumbuhan cepat sebagai penghasil daging, masa panen pendek, dan menghasilkan daging berserat lunak, timbunan daging baik, dada lebih besar dan kulit licin (Rasyaf, 2008). Berbagai macam strain ayam ras pedaging telah beredar dipasar Indonesia memiliki daya produktifitas relatif sama, artinya seandainya terdapat perbedaan, perbedaannya tidak mencolok atau sangat kecil. Adapun jenis strain ayam ras pedaging yang banyak beredar di pasaran adalah: Super 77, Tegel 70, ISA, Kim cross, Lohman 202, Hyline, Vdett, Missouri, Hubbard, Shaver Starbro, Pilch, Yabro, Goto, Arbor arcres, Tatum, Indian river, Hybro, Cornish, Brahma, Langshans, Hypeco-Broiler, Ross, Marshall”m”, Euribrid, A.A 70, H&N, Sussex, Bromo, CP 707 (BPP Teknologi, Kementrian Riset dan Teknologi, 2000) Pemeliharaan ayam pedaging meliputi management (pengelolaan usaha peternakan), breeding (pembibitan), feeding (pakan ternak). Faktor ini selain mempengaruhi pertumbuhan ternak juga mempengaruhi kesehatan ternak yang diakibatkan oleh agen infeksius maupun non-infeksius. Kelemahan ayam 7 8 pedaging adalah memerlukan pemeliharaan secara intensif dan lebih peka terhadap infeksi suatu penyakit (Murtidjo, 1992). Penyebab penyakit infeksius pada ayam cukup kompleks, mulai dari bakteri, virus, protozoa, dan parasit. Beberapa penyakit ayam yang populer di Indonesia antara lain Cronic Respiratory Disease, Coryza, Newcastle disease (ND) atau sering disebut tetelo, gumboro, berak darah, koliseptikemia, dan avian influenza (Murtidjo, 1992). 2.2. Koliseptikemia Koliseptikemia adalah penyakit infeksius yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli (E. coli) patogen. Infeksi E. coli atau koliseptikemia ini dapat terjadi pada ayam pedaging dan petelur dari semua kelompok umur, serta unggas lainnya seperti kalkun dan itik (Charlton et al., 2000). Koliseptikemia terjadi jika Escherichia coli masuk ke dalam sirkulasi darah dan menginfeksi berbagai jaringan melalui lesi pada usus atau saluran pernafasan yang ditimbulkan oleh berbagai sebab. Gejala klinik yang timbul dapat berbentuk gangguan pencernaan dan gangguan pernafasan. Gejala awal biasanya ditandai oleh penurunan nafsu makan, lalu diikuti oleh kelesuan dan bulu berdiri. Ayam yang sakit akan menunjukkan peningkatan frekuensi nafas disertai ngorok (Tabbu, 2000). Nugroho dan Wibowo (2005) mengemukakan bahwa gejala klinis yang teramati pada ayam terinfeksi koliseptikemia yang berumur 15 hari adalah depresi, anoreksia, bulu-bulu kasar, sayap tergantung dan kelemahan umum. Perubahan patologi anatomi yang dapat dilihat berupa perihepatitis, peritonitis dan perikarditis dengan tingkat keparahan yang bervariasi. Penyakit koliseptikemia dapat dimanifestasikan dalam bentuk kelainan organ, seperti: 9 airsacculitis, omfalitis, septikemia, enteritis, coligranuloma, pericarditis, salphingitis, panopthalmitis, arthritis/synovitis. Gambaran PA yang demikian dapat ditetapkan diagnosanya sebagai koliseptikemia. Namun apabila dalam pemeriksaan PA dan HP ditemukan lebih dari satu penyakit dan perubahan pada penyakit tersebut lebih menonjol, maka biasanya koliseptikemia tersebut dianggap sebagai ikutan atau sebagai infeksi sekunder (Tabbu, 2000). Manifestasi penyakit koliseptikemia pada unggas antara lain: 1. Airsacculiti. Air sac menebal dan pada beberapa kasus, terdapat eksudat kaseosa. Biasanya terdapat perikarditis adesif dan perihepatitis fibrinosa. 2. Omfalitis. E. coli dapat diisolasi dalam biakan murni dari tetasan unggas yang mengalami depresi, septicemia, kematian tidak tetap. Tali pusar membengkak, meradang dan unggas demam. 3. septikemia. septikemia disebabkan oleh E. coli yang menyerupai fowl typhoid dan fowl cholera. Terjadi kematian tiba-tiba, mortalitas dan morbiditas tidak tetap. Organ parenkim membengkak dengan kongesti pada muskulus pektoral. Hati berwarna hijau dan bisa terdapat foki nekrotik kecil. 4. Enteritis. Terjadi diare. Pada nekropsi terdapat enteritis, selalu bersama dengan mukus 5. Salphingitis Lesi ini terdapat bersamaan dengan masuknya bakteri coliform dari vagina pada ayam layer. Unggas terinfeksi biasanya mati selama enam bulan pertama setelah infeksi dan tidak pernah bertelur. 10 6. Coligranuloma (Hjarre’s disease). Nodul (granuloma) terdapat sepanjang saluran pencernaan, usus dan hati. Lesi menyerupai tuberkulosis. 7. Sinovitis dan artritis. Unggas yang terinfeksi pincang atau ambruk. 8. Panolphthalmitis. Unggas mengalami hypopyon, biasanya satu matanya buta. 9. Perikarditis. Sebagian besar serotipe E. coli setelah septicemia, menyebabkan perikarditis (Whiteman et al., 1983). Apabila terjadi septikemia, untuk meningkatkan kondisi hewan perlu dilakukan pemberian cairan tubuh dengan larutan glukosa dan mineral melalui mulut (Akoso, 1993). Tindakan pencegahan koliseptikemia lebih ditekankan dengan memperhatikan sanitasi kandang dan lingkungan serta manajemen pakan agar dapat mengurangi tingkat pencemaran E. coli. Pencegahan berbagai penyakit pernapasan, pencernaan dan penyakit yang bersifat imunosupresif hendaklah mendapat prioritas utama (Tabbu, 2000). 2.3. Escherichia coli (E. coli) E. coli merupakan bakteri anaerob fakultatif yang merupakan anggota golongan coliform, E. coli adalah penghuni umum dalam pencernaan manusia dan hewan, dianggap tidak patogen apabila didalam saluran pencernaan dan patogen apabila berada diluar saluran pencernaan (Jawetz et al., 1982). Adapun taksonomi dari Escherichia coli sebagai berikut: Superdomain : Phylogenetica 11 Filum : Proterobacteria Kelas : Gamma Proteobacteria Ordo : Enterobacteriales Family : Enterobacteriaceae Genus : Escherichia Species : Escherichia Coli Ada tiga macam struktur antigen yang penting dalam klasifikasi E. coli yaitu, antigen O (Somatik), antigen K (Kapsel) dan antigen H (Flagella). Determinan antigen (tempat aktif suatu antigen) O terletak pada bagian liposakarida, bersifat tahan panas dan dalam pengelompokannya diberi nomor 1,2,3 dan seterusnya. Antigen K merupakan polisakarida atau protein, bersifat tidak tahan panas dan berinterferensi dengan aglutinasi O, sedangkan antigen H mengandung protein, terdapat pada flagella yang bersifat termolabil. Pada saat ini telah diketahui ada 173 grup serotype antigen O, 74 jenis antigen K dan 53 jenis antigen H. E. coli dapat menghasilkan berbagai jenis toksin seperti endotoksin, enterotoksin dan neurotoksin (Barness dan Gross, 1997). Sebagian besar strain E.coli tidak berbahaya, namun terdapat beberapa yang bersifat patogen. Strain E.coli merupakan flora normal saluran pencernaan, yang menguntungkan host dengan memproduksi vitamin K, atau mencegah pertumbuhan bakteri lain. Sedangkan bakteri E.coli patogen meliputi Enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC), Enteropathogenic Escherichia coli (EPEC), Enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC), Verotoxigenic Escherichia coli (VTEC), Urophatogenic Escherichia coli (UPEC). Avian patogen Escherichia 12 coli (APEC) menyebabkan aerosacculitis, poliserositis, septicemia dan penyakit terutama ekstraintestinal lainnya pada ayam, kalkun dan spesies unggas lainnya (Dho-Moulin dan Fairbrother, 1999). Janben et al. (2001) mengelompokkan E. coli patogenik sesuai dengan gejala klinis yang ditimbulkan antara lain: E. coli penyebab diare, E. coli penyebab septisemia dan Avian Pathogenic Escherichia coli (APEC). Galur APEC merupakan galur yang berhubungan dengan lesi-lesi karakteristik penyakit koliseptikemia pada ayam. 2.3.1. Patogenesa E. coli Penyebab Koliseptikemia Koliseptikemia umumnya disebabkan oleh avian pathogenic E. Coli (APEC). Sejauh ini, APEC didominasi 3 sero grup yaitu O1, O2 dan O78. Bakteri tersebut mampu menyebar melalui peredaran darah sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada berbagai organ (Tabbu, 2000). Disamping itu infeksi E. coli pada embrio ayam dapat menyebabkan radang pada pusar (Barness dan Gross, 1997). Penularan E. coli penyebab koliseptikemia dapat terjadi secara vertikal dan horizontal. Penularan secara vertikal terjadi melalui saluran reproduksi induk ayam, yaitu melalui ovarium atau oviduk yang terinfeksi. Telur yang menetas akan menghasilkan DOC yang tercemar bakteri E. coli. Sedangkan Penularan secara horizontal terjadi secara kontak langsung dengan ayam sakit atau secara tidak langsung melalui kontak dengan bahan/peralatan kandang yang tercemar. Penularan biasanya terjadi secara oral melalui ransum/air minum yang terkontaminasi bakteri melalui saluran pernapasan bersama debu diudara (Tarmudji, 2003). 13 Dalam kondisi normal bakteri E. coli terdapat di dalam saluran pencernaan ayam. Sekitar 10−15 persen dari seluruh bakteri E. coli yang ditemukan di dalam usus ayam yang sehat tergolong serotipe patogen. Bagian usus yang paling banyak mengandung kuman tersebut adalah jejunum, ileum dan sekum. Serotipe E. coli yang terdapat di dalam usus tidak selalu sama dengan serotipe yang ditemukan pada jaringan lain (Tabbu, 2000). Sebagai agen penyakit sekunder, E. coli sering mengikuti penyakit lain, misalnya pada berbagai penyakit pernafasan dan pencernaan yang menyerang ayam (Tarmudji, 2003). Tabbu (2000) menyatakan bahwa Penularan koliseptikemia biasanya terjadi secara oral melalui pakan, air minum atau debu/kotoran yang tercemar oleh E. coli. Debu dalam kandang ayam dapat mengandung 10 5–106 E. coli/gram dan bakteri ini dapat tahan lama, terutama dalam keadaan kering. Apabila debu tersebut terhirup oleh ayam, maka dapat menginfeksi saluran pernafasannya. Kuman E. coli yang dikeluarkan oleh unggas bersama tinja lalu ditularkan melalui makanan dan minuman dan dimakan oleh unggas lain. Faktor virulensi E. coli dipengaruhi oleh ketahanannya terhadap fagositosis, kemampuan perlekatan terhadap epitel sel pernafasan dan ketahanannya terhadap antibodi oleh serum. E. coli patogen mempunyai struktur dinding sel yang disebut “vili”, yang tidak ditemukan pada serotipe yang tidak patogen. Selanjutnya kuman E. coli yang mempunyai vili akan menempel pada saluran pencernaan terutama usus bagian bawah, kemudian E. coli membentuk kolonisasi usus melalui pembentukan mikrokoloni. Kemudian kuman E. coli akan melepaskan enterotoksin sehingga terjadi penurunan absorpsi natrium, sehingga lumen usus 14 meregang serta terjadi peningkatan peristaltik usus yang diteruskan dengan terjadinya diare (Tabbu, 2000). 2.3.2. Morfologi dan Sifat Biakan E. coli Escherichia coli (E. coli) termasuk bakteri Gram negatif berbentuk batang pendek, tidak tahan asam, tercat uniform, tidak membentuk spora, berukuran 2-3 x 0,6 µm, mempunyai flagella peritrikus, bentuk koloni sirkuler, konveks, halus, memfermentasi laktosa, sukrosa dan memproduksi hemolisin. Bakteri ini dapat tumbuh pada kisaran suhu antara 10-46 ºC, pertumbuhan baik pada suhu 20-40 ºC dan pertumbuhan optimum pada suhu 37 ºC (Howard et al.,1987). Kemampuan E. coli dalam menghemolisis dapat menjadi salah satu metode penentuan patogenitas E. coli. Bakteri ini membutuhkan suasana aerob sampai fakultatif anaerob dengan suhu pertumbuhan optimum pada pH 7,0 tapi tumbuh juga pada pH yang lebih tinggi. Koloni E. coli terlihat basah mengkilat, tidak bening, bulat dan dengan tepi yang terlihat halus dan rata. Koloni muda terlihat halus dan semakin tua menjadi granuler kasar (Radji, 2003). Pada media Eosin Methylene Blue (EMB) koloni E. coli tumbuh khas yaitu terlihat berwarna hijau metalik seperti kilap logam dengan koloni berwarna gelap. Bakteri E. coli memproduksi asam dan gas dalam glukosa, maltosa, manitol, gliserol, xylose, rhamnose, sorbitol dan arabinosa, tetapi tidak dalam dekstrin dan inositol. Beberapa strain E. coli memfermentasi laktosa dengan lambat atau tidak sama sekali, fermentasi adonitol, sukrosa, salisin, rafinosa dan dulsitol bervariasi. E. coli positif pada tes methyl red dan negatif pada tes Vogesproskauer dan citrat. (Barness dan Gross, 1997). 15 2.3.3. Resistensi Kuman E. coli Penyebab Koliseptikemia Terhadap Antibiotika Resistensi adalah suatu keadaan berkurangnya pengaruh antibiotik terhadap bakteri atau secara alamiah bakteri tidak sensitif oleh perlakuan antibiotik. Berbagai cara mekanisme resistensi anatara lain melalui penonaktifan obat, perubahan target atau struktur enzim, penurunan akumulasi obat oleh sel, adanya variasi jalur metabolik maupun peningkatan konsentrasi metabolik (Vincent, 1980). Resistensi kuman terhadap antibiotik didapat dari genetik atau non-genetik. Resistensi antibiotika dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu resistensi alami dan resistensi yang didapat. Resistensi alami merupakan sifat dari sifat antibiotika tersebut yang kurang atau tidak efektif terhadapa kuman. Resistensi yang didapat yaitu apabila kuman tersebut sebelumnya sensitif terhadap suatu antibiotika yang kemudian menjadi resisten (Vincent, 1980). Berdasarkan kejadiannya, resistensi dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu: pertama resistensi alamiah, dimana mikroba sejak semula terhadap antibiotik. Kedua resistensi kromosom mikroba yang resisten secara spontan dan sudah tidak peka terjadi karena tergantung pada seleksi kecepatan terjadinya resistensi yaitu mutasi satu tahap dimana resistensi terjadi relatif cepat dan tergantung dosis antibiotika, yang ketiga yaitu resistensi ekstra kromosom, dimana terjadi pemindahan faktor resistensi (faktor R atau plasmid resistensi) dari sel bakteri satu ke sel bakteri yang lainnya melalui konjugasi yaitu diantara dua bakteri terbentuk pillus kelamin yang merupakan suatu saluran protein yang digunakan untuk mengangkut faktor R kemudian 16 dibawa ke pembentukan sel bakteri enzim lain. sehingga Adanya faktor antibiotik R menjadi akan menyebabkan inaktif, merubah permeabilitas sel bakteri terhadap antibiotik dan menurunkan kemampuan ikatan antibiotik terhadap reseptornya (Grifith, 1970). Selain sifat resistensi antibiotik dapat pula terjadi resistensi non-genik, yaitu resistensi terjadi pada kuman dalam keadaan istirahat/inaktivasi metabolik. Bila kuman aktif kembali, maka kuman akan bersifat resisten terhadap antibiotik seperti semula. Resistensi juga dapat terjadi karena resistensi silang, yaitu saat populasi kuman yang resisten terhadap suatu antibiotik dapat resisten pula pada antibiotik lainya yang mempunyai struktur kimia dan mekanisme kerja yang hampir sama (Vincent, 1980). Terjadinya resistensi kuman terhadap antibiotika, karena kuman sering terpapar oleh antibiotika yang nantinya akan menyebabkan kuman akan mempunyai kemampuan untuk mencegah pengaruh antibiotika dengan jalan membentuk selaput sel yang dapat menghambat masuknya antibiotika ke dalam sel kuman (Jawetz et al., 1982). Hal ini sesuai dengan pernyataan Grifith (1970) bahwa pemakaian antibiotik yang monoton dan tanpa prosedur yang benar akan dapat menimbulkan peningkatan resistensi kuman terhadap antibiotik dan kebiasaan memberi antibiotik pada ternak menyebabkan ternak tumbuh lebih cepat tetapi menyebabkan pula peningkatan organisme usus yang resisten terhadap antibiotik. Laporan Zanella et al. (2000) mengemukakan bahwa E. Coli resisten terhadap Tetrasiklin, Linkomisin, Khlorampenikol, Nadilic-acid dan Kanamisin. 17 Penelitian Nugroho et al. (2005) menunjukan bahwa secara umum E coli resisten terhadap Ampisilin, Streptomisin dan Enrofloksasin. Sedangkan pada penelitian Krisnaningsih et al. (2005) menunjukan bahwa E coli resisten terhadap Lincomycin, Danofloxacin, Ampicillin dan Amoxycillin. Dari hasil uji sensitivitas obat terhadap isolat E. coli yang berasal dari lima wilayah peternakan ayam di Jawa dan Bali oleh Poernomo et al. (1992), menunjukkan bahwa E. coli sensitif terhadap Khloramfenikol dan Baytril, tetapi resisten terhadap Neomisin, Eritromisin, Oksitetrasiklin, Deksisiklin dan Streptomisin. Reistensi E. coli terhadap antibiotik dapat disebabkan oleh kemampuan bekteri menghasilkan enzim b-lactamase yang disandi oleh gen dalam plasmid faktor R. mekanisme resistensi terhadap antibiotik yang berhubungan dengan permeabilitas membran, termasuk terjadinya mutasi membrane terluar yang umumnya disandi secara kromosomal sehingga lebih stabil dibandingkan dengan sifat resistensi yang disandi oleh gen pada plasmid (Katzung, 1982) dikutip oleh Krisnaningsih, et al. (2005) Ketidakmampuan antibiotik tersebut melawan E. coli ini, karena obatobatan tersebut sering digunakan oleh peternak untuk pengobatan penyakit bakterial pada ayam. Selain itu, jenis obat tersebut secara umum juga digunakan sebagai obat anti stres dan imbuhan pakan (Tarmudji, 2003). Penggunaan antibiotika dengan dosis yang kurang tepat dapat menimbulkan kegagalan pengobatan yakni berupa resistensi kuman terhadap antibiotika. Adanya resistensi terhadap antibakteri merupakan persoalan utama dalam menangani koliseptikemia (Akoso, 1993). 18 2.4. Antibiotika Antibiotika adalah zat yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang dapat dipergunakan untuk membunuh mikroorganisme jenis lain. Antibiotika ini diperoleh secara alamiah. Keberhasilan suatu pengobatan terhadap penyakit yang disebabkan oleh kuman sangat dipengaruhi oleh ketepatan dalam memilih obat tersebut, disamping itu perlu dipertimbangkan penggunaan antibiotika yang mempunyai efek atau sifat bakteriostatik dan bakteriosidal (Tono dan Hapsari, 1989). Idealnya, zat – zat antibiotik harus mempunyai sifat–sifat sebagai berikut : mempunyai kemampuan untuk merusak atau menghambat mikrobia patogen spesifik, tidak mengakibatkan berkembangnya bentuk resisten, tidak menimbulkan efek samping seperti alergi, kerusakan syaraf, iritasi pada ginjal dan saluran gastrointestinal, tidak melenyapkan flora normal pada hospesnya, dapat diberikan secara oral ataupun suntikan, mempunyai taraf kelarutan yang tinggi dalam cairan tubuh, konsentrasi antibiotik di dalam jaringan atau darah harus dalam jumlah yang cukup. Antibiotik menghambat mikroba melalui mekanisme yang berbeda-beda yaitu: mengganggu metabolisme sel mikroba, menghambat sintesis dinding sel mikroba mengganggu permeabilitas membran sel mikroba menghambat sintesis protein sel mikroba dan menghambat sintesis atau merusak asam nukleat sel mikroba (Tono dan Hapsari, 1989). 2.4.1. Oksitetrasiklin Oksitetrasiklin termasuk dalam golongan tetrasiklin, yang diperoleh dari streptomyces rimosus. Antibiotik ini bersifat bakteriostatik pada konsentrasi 19 rendah dan bakteriosidal pada konsentrasi tingggi, aktif terhadap Gram-positif maupun Gram-negatif. Oksitetrasiklin berbentuk basa, berwarna kuning, berasa pahit dan memeiliki kelarutan lebih besar dari tetrasiklin yaitu yaitu 1g/ml pada suhu 28° dan mudah larut dalam etanol (Pratiwi, 2008). Oksitetrasiklin memiliki spektrum luas, artinya antibiotik ini memiliki kemampuan melawan sejumlah bakteri patogen. Kinerjanya dengan cara menghambat sisntesis protein bakteri pada ribosomnya. Terdapat dua proses dalam masuknya antibiotika ke dalam ribosom bakteri Gram negatif, yaitu pertama disebut difusi pasif melalui kanal hidrofilik, kedua ialah sistem transport aktif. Setelah masuk maka antibiotika akan berikatan dengan ribosom 30S dan menghalangi masuknya tRNA-asam amino pada lokasi asam amino. Secara umum oksitetrasiklin digunakan untuk mengobati infeksi saluran pencernaan, misalnya yang disebabkan oleh kuman E. coli (Bucle dan Williams, 1978). Resistensi bakteri terhadap tetrasiklin dapat muncul bila dihasilkan membran sitoplasma yang berbeda (bentuk perubahan) dan mencegah pengikatan tetrasiklin pada subunit 30S ribosom, sehingga sintesis protein dapat terus berlangsung (Pratiwi, 2008). 2.4.2. Ampisilin Ampisilin adalah antibiotika golongan aminopenisilin berspektrum luas yang bersifat bakteriosidal sekunder terhadap kuman Gram positif maupun Gram negatif, tetapi aktifitasnya terhadap kokus Gram negatif lebih rendah dari penisilin. Bakteri-bakteri yang rentan terhadap Ampisilin antara lain : Streptococcus, Staphylococcus, Cornyabacterium, Fusiformis sp, E. coli, 20 Klebsiella, Shigella, Salmonella, Proteus, Brucella, dan pasteurella (Brander et al., 1991). Ampisilin digunakan untuk pengobatan infeksi bakteri, yang disebabkan oleh bakteri Gram positif maupun Gram negatif. Mengobati infeksi saluran pernafasan, saluran urin, infeksi pencernaan, septikemia, mastitis, dan metritis (Abadi et al., 2013). Ampisilin dalam bentuk asam bebas berbentuk kristal putih yang larut air. Puncak konsentrasi dalam serum diperoleh kurang dari 2 jam, kemudian didistribusikan keseluruh tubuh dan terkonsentrasi dihati dan ginjal dan diekskresikan melalui urin. Pemberian ampisilin secara oral kurang baik dibandingkan dengan amoksisilin. Ampisilin dapat diinaktivasi oleh bakteri penghasil penisilinase. Seperti golongan penicillin lainnya, ampicillin bekerja dengan menghambat sintesis dinding sel yaitu dengan menyerang peptidoglikan (Brander et al., 1991). 2.4.3. Sulfametoksazol Sulfametoksazol adalah antibiotika golongan sulfonamide dengan masa kerja sedang. Antibiotik ini bersifat bakteriostatik terhadap kuman Gram-positif dan beberapa kuman Gram-negatif. Kebanyakan Sulfametoksazol diberikan melalui oral karena absorbsinya cepat di lambung dan usus halus serta didistribusikan ke seluruh jaringan tubuh (Pratiwi, 2008). Penggunaan antibiotik golongan sulfonamid kemudian terdesak oleh antibiotik. Setelah penemuan kegunaan sediaan kombinasi trimetoprim dan sulfametoksazol, penggunaan sulfonamide untuk pengobatan penyakit infeksi tertentu meningkat kembali (Syarif et. al., 2007). Mekanisme kerjanya adalah 21 mengganggu sintesis asam folat lewat hambatan kompetitif terhadap dihidropteroatsintetase (antagonismus folat). Resistensi terhadap sulfonamid dan trimetoprim disebabkan oleh mutasi pada gen pengkode enzim yang terlibat dalam jalur metabolisme sintesis asam tetrahidrofolat. Enzim berubah berfungsi secara normal namun tidak dihambat oleh sulfanamid dan trimetoprim (Pratiwi, 2008).