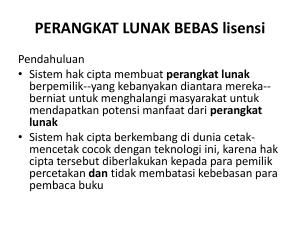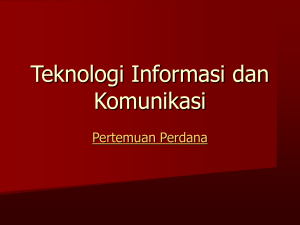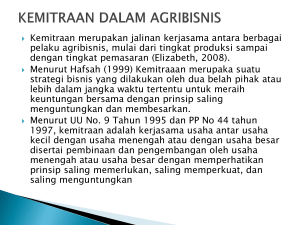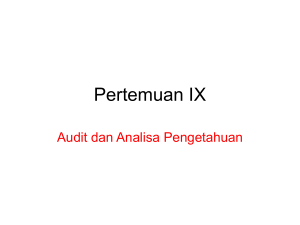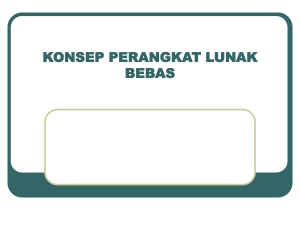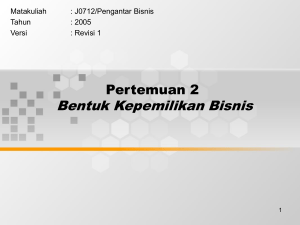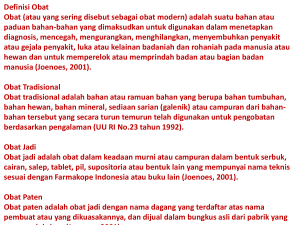139 AKIBAT HUKUM TANAH TIDAK BERSERTIFIKAT YANG
advertisement

... 139 AKIBAT HUKUM TANAH TIDAK BERSERTIFIKAT YANG MENJADI JAMINAN KREDIT Anak Agung Pradnyaswari Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar [email protected] Abstract: Lending process with the assurance that the land has not been certified is basically similar to the provision of credit in general. The difference is the provision of ceiling amount. Binding of security on land that has not been done with a Power of Attorney for Mortgage Impose. Binding of a guarantee is valid until the agreement expires or is paid off the principal. Although Power of Attorney for Mortgage Impose is valid until the loan is repaid, the bank will continue to use the Power of Attorney for Mortgage Impose as a basis for imposition of the Imposition of Mortgage Deed. It is intended that the guarantee is much stronger binding and reduce the risk of loss of the creditors that might arise in the future and provide a strong and secure position for creditors. In the event of default, an effort that is best done through non-litigation is by way of negotiation, by the way this dispute will be resolved quickly, cheaply and easily. Key Words : Credit agreements, mortgages, land is not certified. Pendahuluan Dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dimana uang sebagai alat pembayaran. Dapat dikatakan bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Dalam kegiatan pinjam-meminjam uang yang terjadi di masyarakat dapat diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan utang dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan. Kewajiban untuk menyerahkan jaminan utang oleh pihak peminjam dalam rangka pinjaman uang sangat terkait dengan kesepakatan diantara pihak-pihak yang melakukan pinjam-meminjam uang. 1 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa antara pihak peminjam dengan pihak pemberi pinjaman terdapat suatu ikatan perjanjian. 1 M.Bahsan, 2007, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 2. ... 140 Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua orang atau dua pihak, mengenai halhal pokok yang menjadi objek dari perjanjian. Kesepakatan itu timbul karena adanya kepentingan dari masing-masing pihak yang saling membutuhkan. Perjanjian juga dapat disebut sebagai persetujuan, karena dua pihak tersebut setuju untuk melakukan sesuatu. Menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perjanjian”, kata sepakat berarti suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak. Berdasarkan pengertian kata sepakat tersebut berarti apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain, meskipun tidak sejurusan tetapi secara timbal balik kedua kehendak itu bertemu satu sama lain. 2 Pengertian perjanjian menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih dengan mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, yang terdiri dari empat syarat yaitu: a. Adanya kata sepakat mereka yang mengikat diri; b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; c. Suatu hal tertentu; d. Suatu sebab yang halal. Kegiatan pinjam-meminjam uang yang dikaitkan dengan persyaratan penyerahan jaminan utang banyak dilakukan oleh perorangan dan berbagai badan usaha. Badan usaha umumnya tegas mensyaratkan kepada pihak peminjam untuk menyerahkan suatu barang (benda) sebagai jaminan utang pihak peminjam. Kredit yang diberikan oleh bank tentu saja mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan prospek usaha dari debitur. 3 2 3 R. Soebekti, 1995, Aneka Perjanjian (Cetakan Kesepuluh), Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 26. Hermansyah, 2005, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta, hal. 68 ... 141 Adanya kebutuhan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat menyebabkan kebutuhan akan uang pun semakin meningkat, banyak masyarakat yang berminat menjaminkan benda terutama hak milik atas tanahnya untuk mendapatkan uang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Namun dalam kenyataan tanah yang dijaminkan oleh masyarakat, ada yang belum disertifikatkan. Padahal menurut Pasal 13 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah menentukan bahwa salah satu syarat hak atas tanah yang dapat dijadikan obyek hak tanggungan adalah hak tersebut sesuai ketentuan yang berlaku wajib didaftar dalam daftar umum, dalam hal ini pada Kantor Badan Pertanahan Nasional untuk mendapatkan sertifikat tanah. Hak Tanggungan, menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1996, yaitu jaminan yang dibebankan hak atas tanah, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan suatu ketentuan dengan tanah untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan pada kreditur terhadap kreditur lain. Lembaga Jaminan Hak Tanggungan digunakan untuk mengikat objek jaminan utang yang berupa tanah atau bendabenda yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan. Dengan berlakunya UndangUndang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka hipotek yang diatur oleh KUHPerdata dan credietverband yang sebelumnya digunakan untuk mengikat tanah sebagai jaminan hutang, untuk selanjutnya sudah tidak dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengikat tanah. Perjanjian Kredit dan Jenis-jenis Kredit Kata Kredit berasal dari bahasa Romawi, yakni credere yang artinya percaya, ada juga yang mengartikan sebagai “credo” dan “creditum”, yang arti kesemuanya tersebut adalah kepercayaan, yang dalam Bahasa Inggris disebut “faith” atau “trust”. 4 Dapat dikatakan bahwa antara kreditor (yang member kredit, yang lazimnya bank) dalam hubungan perkreditan dengan debitur (nasabah, penerima kredit), mempunyai kepercayaan bahwa debitur dalam waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit yang bersangkutan. Seseorang yang memperoleh kepercayaan, dengan demikian dasar dari kredit berarti memperoleh kepercayaan. 5 Dalam masyarakat umum istilah kredit sudah tidak asing lagi dan bahkan 4 Gatot Supramono, 1996, Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis, Djambatan, Jakarta, hal. 44. 5 Edy Putra, 1989, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Liberty, Yogyakarta, hal. 1. ... 142 dapat dikatakan populer dan merakyat, sehingga dalam bahasa sehari-hari sudah dicampuradukkan begitu saja dengan istilah utang. 6 Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 yaitu: “ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Buku III KUH Perdata Pasal 1338 yang memberikan hak kepada para pihak untuk membuat dan melakukan kesepakatan apa saja dengan siapa saja, selama mereka memenuhi syarat sahnya perjanjian, dan tidak ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. Pembatasan dalam pembebasan berkontrak terdapat dalam Pasal 1337 KUH Perdata bahwa suatu tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan Undang-undang. Kata kredit memiliki beberapa elemen yang saling berkaitan yakni kemampuan, modal, anggunan dan jaminan serta kondisi ekonomi. Adapun yang dimaksud dengan unsurunsur tersebut adalah: a. Capacity (kemampuan) Seseorang yang mempunyai kemampuan yang lebih akan dipercaya oleh kreditur dalam memberikan kredit, karena dipandang mampu menjalankan usahanya dengan baik. b. Capital (modal) Modal yang cukup menunjang dalam melakukan usaha merupakan pertimbangan bagi kreditur dalam memberikan kredit, karena seseorang kreditur dalam memberikan kredit usaha juga memandang modal dari seorang kreditur. c. Collateral (agunan dan jaminan) Agunan merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan kredut, karena suatu perjanjian kredit tidak dapat terjadi tanpa adanya agunan sebagai jaminan kredit. d. Condition of Economic (kondisi ekonomi) Seorang kreditur dalam memberikan kredit harus memandang prospek usaha debitur karena mempengaruhi pengembalian dari kredit apabila jatuh tempo. Walaupun terdapat berbagai macam pengertian dari para ahli tentang kredit, dapat ditarik beberapa unsur dari kredit antara lain : a. b. c. d. 6 Adanya orang/badan yang memiliki uang, barang atau jasa, dan bersedia untuk meminjamkannya kepada pihak lain, biasanya disebut kreditur. Adanya orang/badan sebagai pihak yang memerlukan/meminjam uang, barang atau jasa yang biasanya disebut debitur. Adanya kepercayaan kreditur terhadap debitur. Adanya janji dan kesanggupan kreditur terhadap kreditur. Rachmadi Usman, 2010, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 236. ... 143 e. Adanya perbedaan waktu, yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa, oleh kreditur dengan saat pembayaran kembali oleh debitur. H.M.A Savelberg menyatakan bahwa kredit merupakan dasar setiap perikatan (verbintenis) dimana seseorang berhak menuntut sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu. 7 Muchdarsyah Sinungan memberikan pengertian kredit sebagai suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lainnya dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada waktu tertentu disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga. 8 Agar suatu perjanjian sah menurut hukum diperlukan 4 (empat) persyaratan sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu : sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit, tanpa perjanjian kredit yang ditanda tangani antara Bank atau Kreditur dengan Debitur, maka tidak aka nada pemberian kredit itu. Perjanjian kredit merupakan ikatan antarabank atau kreditur dengan debitur yang isinya menentukan dan mengatur hak dan kewajiban kedua pihak sehubungan dengan pemberian atau pinjaman kredit. 9 Pemberian kredit oleh pihak bank kepada nasabah bermula dari adanya rasa saling percaya. Kepercayaan dari bank bahwa debitur pada waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama dan dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit dan memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan kredit tersebut. Berkaitan dengan bentuk perjanjian kredit, dalam praktek perbankan didasarkan pada ketentuan sebagai berikut : a. b. 7 Instruksi Presidium Nomor 15/IN/10/66 tentang Pedoman Kebijakan di Bidang Perkreditan tanggal 3 Oktober 1996 jo Surat Edaran Bank Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb tanggal 8 Oktober 1996, Surat Edaran Bank Indonesia Unit I Nomor 2/649/UPK/Pemb tanggal 20 Oktober 1966 dan Instruksi Presidium Kabinet Nomor 10/EK/2/1967 tanggal 6 Pebruari 1967, yang menyatakan bahwa : “Bank dilarang melakukan pemberian kredit dalam berbagai bentuk tanpa adanya perjanjian kredit yang tidak jelas antara bank dan nasabah atau antara Bank Sentral dan bank-bank lainnya.” Oleh karena itu, dalam memberikan kredit dalam berbagai bentuk, wajib dibuatkan perjanjian atau akad kreditnya. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DER dan Surat Edaran Bank Indonesia 27/7/UPPB masing-masing tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Mariam Darus Badrulzaman, 1991, Perjanjian Kredit Bank, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 24 Edy Putra, op.cit, hal. 2 9 Sutarno, 2009, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Alfabeta, Bandung, hal. 98 8 ... 144 bagi bank umum, yang menyatakan bahwa setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis. Perjanjian kredit digunakan dalam berbagai macam jenis-jenis kredit. Jenis kredit ditinjau dari segi tujuan penggunaannya dapat berupa Kredit Produktif, yaitu kredit yang diberikan kepada usaha-usaha yang menghasilkan barang dan jasa sebagai kontribusi dari usahanya. Terdapat dua jenis juga yaitu : Kredit Modal kerja dan kredit investasi dan Kredit Konsumtif, yaitu Kredit yang diberikan kepada orang perorangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Jenis kredit ditinjau dari segi jangka waktunya dapat berupa Kredit Jangka Pendek, yaitu Kredit yang memiliki jangka waktu maksimum 1 (satu) tahun, Kredit Jangka Menengah, yaitu Kredit yang berjangka waktu antara 1 (satu) hingga 3 (tiga) tahun dan Kredit Jangka Panjang, yaitu Kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun. Kredit ini pada umumnya adalah kredit investasi yang bertujuan untuk menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi dan pendirian proyek baru. 10 Jaminan Kredit Dalam Praktik Perbankan Istilah Jaminan adalah berasal dari terjemahan kata Zekerheid atau Cautie yaitu mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggung jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. Jaminan menurut Mariam Darus Badrulzaman adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditor untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan. 11 Dalam praktik perbankan masalah jaminan ini sangat penting artinya, terutama yang berhubungan dengan kredit yang dilepas kepada nasabahnya. Dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah/debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam Pasal 8 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 mengemukakan bahwa berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah/ debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan itulah yang diartikan sebagai 10 Daeng Naja, 2005, Hukum Kredit dan Bank Garansi The Bankers Hand Book, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 125. 11 Mariam Darus Badrulzaman, Permasalahan Hukum Hak Jaminan, dalam Hukum Bisnis, Volume 11, 2000, hal. 12 ... 145 Jaminan Kredit. Berdasarkan rumusan diatas tersebut dapat diketahui bahwa kredit itu merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur. Dalam perjanjian ini bank sebagai pemberi kredit percaya terhadap nasabah dalam jangka waktu yang disepakatinya akan dikembalikan (dibayar) lunas. 12 Jaminan Kebendaan adalah salah satu bentuk jaminan yang lazim dipergunakan dalam kegiatan pinjam-meminjam di bank. Jaminan kebendaan adalah hak yang memberikan kepada seorang kreditur kedudukan yang lebih baik, karena kreditur didahulukan dan dimudahkan dalam mengambil pelunasan atas tagihannya atas hasil penjualan benda tertentu atau sekelompok benda tertentu milik debitur. 13 Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang termasuk kedalam jenis jaminan kebendaan yaitu : a. b. c. d. 12 Gadai, istilah gadai berasal dari terjemahan kata pond (bahasa belanda) atau pledget pawn (bahasa inggris). Gadai merupakan jaminan utang yang bersifat jaminan kebendaan dan salah satu lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk mengikat objek jaminan utang yang berupa benda bergerak. 14 Gadai diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUHPerdata. Hipotik, merupakan jaminan utang yang bersifat jaminan kebendaan dan salah satu lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk mengikat objek jaminan utang yang berupa benda tidak bergerak. Hipotek diatur dalam Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 KUHPerdata. Yang dimaksud Hipotek dalam Pasal 1162 KUHPerdata adalah suatu hak kebendaan atas suatu benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pekunasan suatu perikatan. Hak Tanggungan merupakan jaminan utang yang bersifat jaminan kebendaan dan salah satu lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk mengikat objek jaminan utang yang berupa benda tidak bergerak. Sejak berlakunya UndangUndang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta bendabenda yang berkaitan dengan tanah, maka pemberian jaminan atas tanah dan hak-hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria hanya dapat dilakukan dengan Hak Tanggungan, hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Tanggungan. Objek jaminan yang dapat dibebani dengan hak tanggungan yaitu hak-hak atas tanah antara lain : hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai baik hak pakai atas hak milik maupun hak pakai atas negara, hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut dan merupakan hak milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas dan dinyatakan di dalam akta pemberian hak atas tanah yang bersangkutan. Jaminan Fidusia merupakan jamian utang yang bersifat jaminan kebendaan dan salah satu lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk mengikat objek jaminan utang yang berupa benda bergerak dan beberapa benda tidak bergerak Adrian Sutedi, 2010, Hukum Hak Tanggungan, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 23 J.Satrio, 2007, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 12 14 Salim HAL. S, 2004, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 25 13 ... 146 khususnya benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan Hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Fidusia diatur dalam Undang-Undang No. 4 2 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 15 Perjanjian kredit merupakan salah satu jenis perjanjian baku, dimana isi atau klausula-klausula perjanjiannya telah ditentukan atau dituangkan dalam bentuk formulir atau blanko yang kemudian akan diisi oleh pihak deitur atau peminjam uang dengan menyertakan tanda tangan serta cap jempol. Perjanjian dengan jaminan atau anggunan harus dibuatkan pengikatan hukum dalam bentuk notariil, baik berupa pengikatan dengan menggunakan akta fidusia, surat kuasa membebankan hak tanggungan dan akta pembebanan hak tanggungan. Jaminan atau anggunan yang dapat diterima oleh pihak pemberi kredit dapat berupa Benda bergerak yang dibedakan atas benda bergerak berwujud, dan benda bergerak tak berwujud dan juga benda tidak bergerak antara lain : Tanah hak milik, tanah hak guna bangunan dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat HGB, tanah hak guna usaha dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat HGU, dan tanah hak milik yang belum disertifikatkan berupa : Girik, petok D, Letter C. Akibat Hukum Kredit Dengan Jaminan Tanah yang Belum Bersertifikat Lazimnya syarat-syarat yang biasanya digunakan suatu badan tertentu yang menyediakan fasilitas kredit kepada peminjam kredit yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP); Kartu Keluarga (KK); Surat Nikah (jika sudah menikah); Bukti Pembayaran PBB; Izin Usaha; Surat Keterangan Usaha; Rekening Listrik dan Rekening Telepon dan Bukti Usaha. Proses pemberian kredit dengan jaminan tanah yang belum bersertifikat pada dasarnya hampir sama dengan pemberian kredit secara umum yang membedakan adalah pemberian jumlah plafond. Pengikatan jaminan atas tanah yang belum bersertifikat dilakukan dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, dan berlaku hingga perjanjian pokok berakhir atau lunas, walaupun SKMHT tersebut berlaku hingga kredit tersebut lunas pihak bank akan tetap mempergunakan SKMHT tersebut sebagai dasar dibuatnya APHT agar pengikatan jaminannya lebih kuat dan mengurangi resiko kerugian dari pihak kreditor yang mungkin akan timbul di kemudian hari dan memberikan kedudukan kuat dan aman bagi para kreditor. 15 M.Bahsan, op.cit, hal. 9 ... 147 Adapun prosedur pengikatan jaminan tanah yang belum bersertifikat didahului dengan dibuatnya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) meliputi beberapa tahapan yakni : a. Adanya surat pengakuan hutang sebagai perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pokok yang ditandatangani oleh pihak kreditur dan debitur. b. Pihak debitur dan kreditur menghadap notaris/PPAT untuk membuat SKMHT dengan membawa surat pengakuan hutang sebagai dasar dibuatnya SKMHT dan terdapat syarat-syarat antara lain : adanya surat penguasaan tanah milik debitur, adanya surat dari aparat desa yang menyatakan tanah milik debitur bukan tanah yang bersengketa, adanya bukti pembayaran pajak tanah, dan surat penguasaan fisik bidang tanah. c. Dibuatlah SKMHT di kantor notaris/PPAT, untuk tanah yang belum bersertifikat pada umumnya harus juga ada saksi dari pihak aparat desa. d. Setelah SKMHT dibuat, dilakukanlah penanda tanganan SKMHT oleh pihak kreditur, debitur, notaris/PPAT juga para saksi. Pihak debitur telah memberikan kuasa kepada pihak kreditur untuk dapat membebankan hak tanggungan pada jaminan atas tanah yang diberikan oleh pihak debitur selanjutnya apabila pihak kreditur menginginkan dengan adanya SKMHT ini, pihak kreditur dapat menggunakan kuasanya sebagai dasar untuk membuat pengikatan jaminan dalam bentuk Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) yang kemudian akan didaftarkan sehingga dapat memperoleh Sertifikat Hak Tanggungan sebagai bukti tanah tersebut telah dibebani hak tanggungan. Menurut ketentuan Pasal 15 ayat 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah, ditentukan bahwa ketentuan masa berlaku SKMHT 1 (satu) bulan untuk hak atas tanah yang sudah terdaftar dan 3 (tiga) bulan untuk hak atas tanah yang belum terdaftar. Namun ketentuan ini tidak berlaku untuk jaminan kredit program, kredit kecil, kredit kepemilikan rumah, dan sejenisnya. Adapun proses pembebanan Hak Tanggungan dilaksanakan melalui 2 tahap kegiatan, yaitu: 1. 2. Tahap pemberian Hak Tanggungan, dengan dibuatnya Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) oleh PPAT, yang didahului dengan perjanjian utang-piutang yang dijamin. Tahap pendaftaran Hak Tanggungan oleh Kantor Pertanahan, yangmerupakan saat lahirnya Hak Tanggungan yang dibebankan. ... 148 Isi dari APHT terdiri dari yang wajib dicantumkan (dimuat) dan yang tidak wajib dicantumkan (fakultatif). Berdasarkan Pasal 11 UUHT, isi di dalam APHT yang wajib dicantumkan meliputi: a. b. c. d. e. Nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan Domisili para pihak, apabila diantara mereka ada yang berdomisili di luar Indonesia, maka harus dicantumkan salah satu domisili yang ada di Indonesia, dan dalam domisili pilahan itu tidak dicantumkan maka kantor PPAT tempat pembuatan APHT dianggap sebagai domisili yang dipilih. Penunjukan secara jelas utang atau utang-utang yang dijamin. Penunjukan utang dan utang-utang yang dijamin meliputi nama dan identitas debitur yang bersangkutan. Nilai tanggungan adalah suatu pernyataan sampai sejumlah batas utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan yang bersangkutan. Uraian yang jelas mengenai obyek Hak Tanggungan. Uraian ini meliputi rincian mengenai sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan atau bagi tanah yang belum terdaftar sekurang-kurangnya memuat uraian kepemilikan, letak, batas-batas dan luas tanahnya. Pemberian kredit dengan jaminan tanah yang belum bersertifikat hal ini dampaknya adalah proses pengikatan jaminan dan pembebanan hak tanggungan akan lebih lama karena membutuhkan waktu untuk dan proses yang lebih panjang dan hal ini mempermudah pihak kreditur dalam hal terjadinya wanprestasi. Langkah pengamanan secara represif dilakukan untuk menyelesaikan kredit-kredit yang mengalami ketidaklancaran karena debitur wanprestasi antara lain : a. b. c. Surat Peringatan ini diberikan kepada debitur bahwa jangka pengembalian sudah lewat dan debitur masih mempunyai tunggakan pinjaman selama tiga (3) bulan berturut-turut. Di dalam surat peringatan ini terdapat tiga (3) kali surat peringatan, yaitu surat peringatan I, surat peringatan II, dan surat peringatan III yang masingmasing memiliki jangka waktu yaitu15 hari dan jarak antara surat peringatan I ke surat peringatan II selama 7 hari begitupun dari surat peringatan II ke surat peringatan III. Surat Somasi akan dilayangkan bila sampai surat peringatan ke III tetapi debitur masih belum melakukan prestasinya maka sekitar tiga (3) minggu setelah surat peringatan ke III tersebut maka dari pihak kreditur akan melakukan somasi kepada pihak debitur. Penyitaan dilakukan jika setelah diberikannya surat somasi kepada debitur tetapi debitur belum juga melakukan prestasinya, maka kredit dinyatakan macet dan debitur dinyatakan wanprestasi. Dan setelah usaha-usaha yang dilakukan oleh kreditur mengalami kegagalan maka kreditur akan melaksanakan haknya dengan cara melelang barang jaminan untuk melunasi hutang debitur, ataupun dilakukan melalui jalur pengadilan. Bila terjadi wanprestasi, upaya yang paling baik dilakukan adalah melalui jalur non litigasi yaitu dengan cara negosiasi, melalui cara ini sengketa yang terjadi akan dapat diselesaikan dengan cepat, tidak berlarut-larut dan biaya yang dikeluarkan pun tidak banyak. ... 149 Penutup Pemberian kredit dengan jaminan tanah belum bersertifikat dilakukan pengikatan Surat Pengakuan Hutang sebagai perjanjian kredit kemudian dibuatkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan di hadapan notaris/PPAT. Dokumen tersebut dipergunakan kreditur sebagai dasar dibuatnya pengikatan jaminan dalam bentuk Akta Pembebanan Hak Tanggungan yang kemudian akan didaftarkan untuk memperoleh Sertifikat Hak Tanggungan. Tanah yang belum bersertifikat bisa dijadikan jaminan oleh debitur yang ingin meminjam sejumlah uang, prosedurnya lebih panjang dan rumit. Bila terjadi wanprestasi, yang dapat dilakukan untuk menyelesaikannya adalah dengan jalan non litigasi (dengan surat peringatan, somasi) ataupun litigasi/pengadilan. Dalam hal jaminan kredit berupa benda tak bergerak seperti halnya tanah, sebaiknya tanah yang dijaminkan adalah tamah yang sudah bersertifikat, hal ini sangatlah penting untuk menghindari dari kerugian dan dalam proses pengikatan jaminan. Sertifikat tanah tersebut adalah merupakan bukti sah kepemilikan tanah, dan dapat dijadikan bukti yang sempurna bila suatu saat nanti terjadi sengketa diantara para pihak. Bila terjadi wanprestasi, upaya yang paling baik dilakukan adalah melalui jalur non litigasi yaitu dengan cara negosiasi, melalui cara ini sengketa yang terjadi akan dapat diselesaikan dengan cepat, tidak berlarut-larut dan biaya yang dikeluarkan pun tidak banyak. DAFTAR PUSTAKA BUKU Badrulzaman, Mariam Darus, 1991, Perjanjian Kredit Bank, Citra Aditya Bakti, Bandung. Bahsan, M., 2007, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hermansyah, 2005, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta. Naja, Daeng, 2005, Hukum Kredit dan Bank Garansi The Bankers Hand Book, Citra Aditya Bakti, Bandung. Putra, Edy, 1989, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Liberty, Yogyakarta. Salim H.S, 2004, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Raja Grafindo Persada. Satrio, J., 2007, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, Citra Aditya Bakti, Bandung. Soebekti, R. 1995, Aneka Perjanjian (Cetakan Kesepuluh), Citra Aditya Bakti, Bandung. Supramono, Gatot, 1996, Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis, Djambatan, Jakarta. Sutarno, 2009, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Alfabeta, Bandung. ... 150 Sutedi, Adrian, 2010, Hukum Hak Tanggungan, Sinar Grafika, Jakarta. Usman, Rachmadi, 2010, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. MAKALAH Mariam Darus Badrulzaman, Permasalahan Hukum Hak Jaminan, dalam Hukum Bisnis, Volume 11, 2000, hal.12. ... 151 EFEKTIFITAS PASAL 69 UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2001 TENTANG LISENSI PATEN BAGI KEPENTINGAN ALIH TEKNOLOGI DI INDONESIA IGN Parikesit Widiatedja Fakultas Hukum Universitas Udayana [email protected] Abstract: Patent license has been granted to Indonesia as a means of accelerating transfer of technology. Desiring the early achievement of its purpose, Indonesia was definetely elaborated a procedural system of patent license in article 69 law number 14 of 2001 concerning patent. Its effectiveness could be analyzed from legal substance, legal structure and legal culture which all aspects were mutually influenced for the particular interests of Indonesia with a view to transfer of technology. Key words: Effectiveness, Patent license, Transfer of Technology Pendahuluan Memasuki era milenium ketiga, berbagai perubahan terjadi di berbagai lini kehidupan dan terjadi dalam kurun waktu yang sangat cepat. Beragam implikasi pun lahir yang kesemuanya bermuara pada globalisasi dan liberalisasi di segala bidang. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) menjadi salah satu bidang yang terkena imbas dari fenomena kontemporer tersebut. Mengingat potensi nilai ekonomi yang dihasilkan, HaKI pun menjadi isu yang menarik perhatian dunia beberapa tahun terakhir. Pada tanggal 15 april 1994 di Marrakesh, Maroko, negara-negara peserta perundingan yang dikenal sebagai Putaran Uruguay, menyepakati suatu aturan perdagangan internasional yang baru sebagai penegasan terhadap aturan-aturan umum dalam GATT. Selain menyepakati terbentuknya lembaga perdagangan internasional atau World Trade Organization (WTO), Persetujuan yang menjadi cikal bakal perluasan liberalisasi perdagangan ini juga menetapkan norma-norma dan standar substantif minimun untuk perlindungan HaKI, termasuk kewajiban untuk meratifikasi konvensi internasional mengenai HaKI yang relevan seperti : The Paris Convention, The Rome Convention,The Bern Convention dan The Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits. 16 Paten telah menjadi subsistem terpenting dalam HaKI khususnya berkenaan dengan pemanfaatan teknologi. Teknologi merupakan obyek pengaturan paten terkait dengan peranannya sebagai faktor penentu dalam pertumbuhan dan perkembangan industri. 16 OK.Saidin, 2003. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 55 ... 152 Sebagai ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam proses industri, teknologi jelas lahir dari kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan. Proses yang nantinya selalu melibatkan tenaga dan pikiran, waktu dan biaya yang sangat besar. 17 Pengaturan mengenai Paten di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No 14 Tahun 2001. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi konvensi-konvensi Internasional di bidang Paten yakni Konvensi Paris melalui Keppres No. 15 tahun 1997, Patent Coorporation Treaty melalui Keppres No. 16 tahun 1997 dan Bern Convention melalui Keppres No. 19 tahun 1997. Berbicara mengenai alih teknologi, paten merupakan salah satu media yang sanggup mendukung dan mengupayakan proses alih teknologi khususnya bagi negara berkembang dalam upaya mengejar ketertinggalannya. Dalam keadaan seperti ini, lisensi paten menjadi salah satu cara yang paling efektif dalam kegiatan alih teknologi. Ketentuan yang selanjutnya diatur dalam Pasal 69 Undang-undang No. 14 Tahun 2001. Lisensi merupakan suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan, yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin. Tanpa adanya izin ini, maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. 18 Lisensi dalam paten merupakan suatu perjanjian yang pada dasarnya hanya bersifat pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari paten dalam jangka waktu dan syarat-syarat tertentu. Dengan adanya lisensi dalam paten, maka setiap pihak dapat memanfaatkan tiap teknologi yang dipatenkan yang tentunya sangat bermanfaat dalam proses alih teknologi khususnya terkait teknologi-teknologi yang berasal dari negara maju. Pada kenyataannya, proses alih teknologi tidak selamanya menjanjikan kontribusi positif. Faktor yang patut diwaspadai ialah potensi ketergantungan diantara negara-negara berkembang yang notebene adalah pihak yang menerima lisensi. Demikian pula dengan kedudukan dan posisi tawar dari pihak negara berkembang yang cenderung berada di posisi inferior. Kondisi yang tentunya sangat berbahaya karena kelak akan menimbulkan suatu gap yang semakin besar diantara negara maju dan berkembang khususnya dalam pemanfaatan teknologi. Untuk itulah penulis mengajukan tulisan mengenai “Efektifitas Pasal 69 UndangUndang No. 14 Tahun 2001 Tentang Lisensi Paten Bagi Kepentingan Alih Teknologi di 17 18 Richard Burton Simatupang, 2003, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 76 Gunawan Widjaya, 2001, Seri Hukum Bisnis Lisensi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 3 ... 153 Indonesia” dimana penulis akan melihat sejauh mana keefektifan dari pemberian lisensi paten ini mampu menjadi media atau sarana proses alih teknologi di Indonesia. Mekanisme Pengaturan Lisensi Paten a. Dalam Konvensi Paris Konvensi Paris mengatur tentang hak milik perindustrian yang ditandatangani di Paris tanggal 20 Maret 1883 dan telah mengalami beberapa kali revisi dan penyempurnaanpenyempurnaan. Sampai pada tanggal 1 Januari 1988, sebanyak 97 negara menjadi anggota konvensi ini. Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi ini berdasarkan Keppres No.24 Tahun 1979 pada tanggal 10 Mei 1979. Melalui keppres ini pula,”Convention Establishing the World Intellectual Property Organization” (WIPO) telah diratifikasi. 19 Yang menjadi objek perlindungan dalam konvensi Paris meliputi Patent, utility models, industrial design, trade mark, trade names, indication of source or appellation of origin. Terkait dengan lisensi paten, Konvensi Paris mengatur mengenai lisensi wajib dalam paten. Ketentuan Pasal 5A Konvensi Paris menyatakan bahwa tiap negara boleh mengambil tindakan hukum/legislatif yang mengatur cara pemberian lisensi wajib. Lisensi wajib ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan yang mungkin disebabkan oleh adanya hak eksklusif yang diberikan paten, seperti tidak dilaksanakannya paten atau pelaksanaannya yang tidak cukup baik. b. Dalam Patent Coorperation Treaty (PCT) Patent Coorperation Treaty (PCT) didirikan pada tanggal 19 Juni 1970 di Washington dalam suatu konferensi pada diplomat dari 78 negara dan 22 organisasi internasional. PCT telah diubah sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 1970 dan tahun 1984. Tujuan PCT ialah agar permohonan internasional paten mendapat beberapa perlindungan di beberapa negara. Untuk itu si pemohon harus mengajukannya di setiap negara dimana perlindungan itu dikehendaki. Terkait dengan lisensi paten dan alih teknologi, PCT juga memberikan bantuan teknik yang merupakan perhatian khusus bagi negara-negara berkembang. PCT sepakat bahwa biro internasional (WIPO) dengan biaya rendah harus memberikan pengetahuan teknik dan teknologi bagi negara-negara tersebut. Selanjutnya sebuah komisi bantuan teknik telah dibentuk yang bertugas untuk menyelenggarakan dan mengawasi bantuan teknik 19 OK Saidin,op.cit, hal. 308 ... 154 dalam mengembangkan sistem paten secara wilayah dan secara terpisah. 20 Keberadaan PCT secara tidak langsung telah mengakomodiir adanya suatu pelaksanaan lisensi paten, mengingat proses alih teknologi seperti yang diatur dalam PCT salah satunya dilakukan melalui pemberian lisensi dalam paten. c. Dalam TRIPs ( Trade Related Aspect of Intellectual Property Right ) Dalam Kesepakatan TRIPs yang menjadi bagian inheren dari WTO, ketentuan mengenai lisensi paksa/ wajib dapat terlihat di bawah section 5 tentang paten, yaitu dalam ketentuan Pasal 31 TRIPs. Secara umum TRIPs menyebutkan adanya empat alasan pemberian lisensi paksa antara lain : 21 1. karena keperluan yang sangat mendesak 2. kepentingan praktek persaingan usaha 3. penggunaan non-komersial untuk kpentingan publik 4. adanya saling ketergantungan d. Dalam ketentuan hukum di Indonesia Pengaturan mengenai lisensi paten di Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. Lisensi diatur dalam Pasal 69 sampai dengan pasl 73 Bagian Kedua Bab V tentang Lisensi dan Pasal 74 sampai dengan Pasal 87 Bagian Ketiga Bab V tentang Lisensi wajib. Dalam Pasal 69 disebutkan bahwa : (1) Pemegang Paten berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. (2) Kecuali jika diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Ini berarti bahwa dalam lisensi paten, diberikan hak kepada pemegang lisensi untuk ; a. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten; b. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a. c. Dalam hal Paten-proses, larangan terhadap pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan Paten-proses yang dimilikinya. 20 21 Ibid, hal. 312. Ibid., hal. 314 ... 155 Dalam Pasal 70 disebutkan pula bahwa Pemegang Paten tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. Selanjutnya mengenai batasan lingkup perjanjian lisensi paten disebutkan dalam Pasal 71 yang menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi tidak boleh memuat ketentuan, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya, dan yang berkaitan dengan Invensi yang diberi Paten tersebut pada khususnya. Ketentuan mengenai lisensi wajib dalam Undang-undang paten diatur dalam Pasal 74 hingga Pasal 87. Lisensi wajib merupakan Lisensi untuk melaksanakan Paten yang diberikan berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal atas dasar permohonan. Permohonan lisensi wajib hanya dapat dilakukan jika paten yang diberikan perlindungan tersebut tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sepenuhnya di Indonesia oleh pemegang paten atau dilaksanakan dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat. Pasal 76 ayat 1 menyatakan bahwa lisensi wajib hanya diberikan apabila: a. Pemohon dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa ia: 1. mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri Paten yang bersangkutan secara penuh; 2. mempunyai sendiri fasilitas untuk melaksanakan Paten yang bersangkutan dengan secepatnya; dan 3. telah berusaha mengambil langkah-langkah dalam jangka waktu yang cukup untuk mendapatkan Lisensi dari Pemegang Paten atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar, tetapi tidak memperoleh hasil; dan b. Direktorat Jenderal berpendapat bahwa Paten tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia dalam skala ekonomi yang layak dan dapat memberikan manfaat kepada sebagian besar masyarakat Mekanisme Pengaturan Pelaksanaan Alih Teknologi a. Dalam TRIPs Dalam Pasal 7 dan Pasal 8 TRIPs dapat diketahui bahwa masalah alih teknologi menjadi perhatian pokok dalam TRIPs. Ketentuan Pasal 7 secara tegas mengatakan pentingnya alih teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi dari negara peserta TRIPs. Dalam Pasal 8 ditekankan pada perlunya perlindungan pada kesejahteraan masyarakat dan gizi, serta untuk menggalakkan sektor-sektor yang vital untuk kepentingan publik yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan teknologi dan sosio ekonomis negara peserta TRIPs. ... 156 b. Dalam WIPO ( World Intellectual Property Organization) Dalam Background Reading Material on Intellectual Property yang diterbitkan oleh WIPO, disebutkan tiga macam cara yang dapat ditempuh dalam alih teknologi meliputi : bentuk penjualan atau pengalihan teknologi, melalui pemberian lisensi dan dengan knowhow agreements. Selanjutnya disebutkan pula lima cara lain yang dapat dilakukan oleh negara berkembang untuk melakukan alih teknologi yaitu: melalui importasi barang-barang modal,dengan waralaba dan program distribusi, perjanjian manajemen dan konsultasi,turn key project dan joint venture agreement. 22 c. Dalam ketentuan hukum di Indonesia Ketentuan pelaksanaan mengenai alih teknologi lebih lanjut dapat terlihat melalui Undang-undang No 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dalam Undang-undang tersebut, alih teknologi merupakan pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada di lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya. Terkait dengan alih teknologi dalam bidang HaKI, menurut Pasal 17 dikatakan bahwa Kerja sama internasional dapat diusahakan oleh semua unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan alih teknologi dari negara-negara lain serta meningkatkan partisipasi dalam kehidupan masyarakat ilmiah internasional. Ketentuan ini dipertegas lewat Pasal 23 yang menyatakan bahwa Pemerintah menjamin perlindungan bagi HaKI yang dimiliki oleh perseorangan atau lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan alih teknologi di Indonesia, Undang-Undang No 14 Tahun 2001 tidak secara eksplisit menyatakan perlunya suatu alih teknologi, namun dengan adanya ketentuan mengenai lisensi paten dalam Undang-undang ini, maka secara tidak langsung mengamanatkan suatu proses alih teknologi yang dapat dilakukan melalui pemberian lisensi paten. Efektifitas Pemberian Lisensi Paten Bagi Kepentingan Alih Teknologi a. Ditinjau dari Substansi Hukum Dari substansi Undang-undang No 14 tahun 2001, terdapat beberapa permasalahan terkait pemberian lisensi paten bagi kepentingan alih teknologi di Indonesia, permasalahanpermasalahan ini antara lain: 22 Yayasan Klinik HaKI, 1999, Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten dan Merek dan Terjemahan Konvensi-Konvensi di Bidang HaKI, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 78. ... 157 Sifat Eklusifitas dari Perjanjian Pemberian Lisensi Paten Dalam perjanjian lisensi paten, dikenal 2 jenis perjanjian, yakni lisensi paten yang bersifat eksklusif dan lisensi paten yang bersifat non-eksklusif. Dalam Undang-undang No 14 tahun 2001 diatur hak-hak khusus untuk pemilik paten atau pemegang paten untuk membuat, menggunakan, atau menjual produk atau proses yang dipatenkan olehnya sendiri atau memberikan kepada orang lain lisensi untuk membuat, menggunakan atau menjual produk atau proses yang dipatenkan tersebut. Perbedaan antara lisensi yang bersifat eksklusif dan non-ksklusif tidak diuraikan dengan jelas. Pembatasan terperinci dari hak-hak khusus untuk pemilik paten yang memberikan lisensi eksklusif atau non-eksklusif tidak tercantum secara tegas dalam Undang-undang ini. Dalam Pasal 69 Undang-undang 14 Tahun 2001 hanya disebutkan bahwa pemilik paten berhak untuk memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan perjanjian lisensi dan meliputi ruang lingkup semua tindakan selama jangka waktu lisensi di seluruh wilayah Indonesia. Secara implisit, sesuai dengan Pasal 70 yang menyatakan bahwa kecuali diperjanjikan lain, pemegang paten tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatannya, maka dapat dikatakan bahwa jenis perjanjian lisensi paten yang dianut di Indonesia adalah bersifat noneksklusif. Namun batasan seperti apa pembagian eksklusif dan non eksklusif tidak dicantumkan dalam undang-undang ini. Dengan tidak diaturnya secara tegas jenis perjanjian lisensi paten dalam Undangundang 14 Tahun 2001, maka kondisi ini dalam prakteknya akan melemahkan posisi dari penerima lisensi karena hanya berdasarkan kepada perjanjian antara kedua belah pihak tanpa memperhatikan keeksklusifannya. Lemahnya posisi penerima lisensi akan berakibat tidak maksimalnya pemanfaatan teknologi yang dilakukan. Kenyataan ini diperparah oleh kecenderungan pihak penerima lisensi yang kebanyakan berasal dari negara berkembang yang cenderung memiliki posisi tawar lemah jika mengadakan suatu perjanjian dengan pihak-pihak yang berasal dari negara maju. Sistem Pembayaran Royalti Royalti merupakan bagian yang penting dari perjanjian lisensi paten yang akan mempengaruhi hubungan antara pemberi dan penerima lisensi. Bagi pemberi lisensi, royalti adalah imbalan baginya karena telah menghabiskan waktu dan biaya penelitian dan percobaan untuk memperoleh penemuan baru itu. Sehingga sedapat mungkin pemberi lisensi atau pemilik paten berharap untuk memperoleh royalti yang tinggi dari penerima lisensi. ... 158 Sampai sekarang di Indonesia, perjanjian lisensi masih didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Tidak ada aturan yang membatasi para pihak yang terlibat dalam perjanjian lisensi. Dengan demikian belum ada aturan yang tegas tentang berapa besarnya pembayaran royalti yang harus dibayarkan oleh penerima lisensi. 23 Dalam Pasal 78 Undangundang No. 14 tahun 2001, mekanisme pembayaran royalti hanya dijelaskan dalam lisensi wajib saja, dimana dikatakan bahwa besarnya royalti yang harus dibayarkan dan cara pembayarannya ditetapkan oleh Direktorat Jenderal. Penetapan besarnya royalti dilakukan dengan memperhatikan tata cara yang lazim digunakan dalam perjanjian liisensi paten atau perjanjian lain yang sejenis. Terhadap lisensi biasa, maka mekanisme pembayaran royalti diserahkan kepada perjanjian diantara para pihak. Tentang Jangka Waktu Lisensi Terkait jangka waktu lisensi,dalam Pasal 76 ayat 3 Undang-undang 14 tahun 2001 dikatakan bahwa lisensi-wajib diberikan untuk jangka waktu yang tidak lebih lama daripada jangka waktu perlindungan Paten. Sedangkan mengenai lisensi biasa dapat disepakati berdasarkan persetujuan para pihak. Mekanisme mengenai jangka waktu lisensi ini bisa saja menimbulkan berbagai permasalahan karena tidak dicantumkan dengan tegas mengenai apakah penerima lisensi masih harus membayar royalti meskipun paten itu telah berakhir atau kadaluwarsa atau telah menjadi milik umum? Atau apakah penerima lisensi atau orang lain harus menyatakan kepada pemberi lisensi jika ia ingin memanfaatkan paten terhadap paten yang telah menjadi milik umum itu? Inilah yang nampaknya belum diatur secara tegas dalam undang-undang paten di Indonesia. Persyaratan Sub-Lisensi Belum ada peraturan yang membatasi apakah penerima lisensi atau penerima transfer teknologi dapat membuat perjanjian sub-lisensi atau tidak dengan pihak ketiga. Undang-undang 14 Tahun 2001 hanya mengatur kewenangan pemilik atau pemegang paten. Kewenangan penerima lisensi untuk melakukan sub-lisensi bergantung pada perjanjian lisensi paten itu sendiri. Dengan tidak ada pembagian secara tegas mengenai jenis perjanjian lisensi paten di Indonesia, maka ketentuan mengenai sub-lisensi ini sepenuhnya tergantung dari perjanjian para pihak, apabila penerima lisensi memiliki posisi tawar yang kuat, maka penerima lisensi dapat saja mengadakan perjanjian sub-lisensi, tetapi bila pemberi lisensi 23 Insan Budi Maulana,1996, Lisensi Paten, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 41 ... 159 yang lebih kuat maka perjanjian sub-lisensi tentu tidak dapt dilaksanakan karena dianggap merugikan pihak pemberi lisensi itu. Pembatasan Lingkup Lisensi Dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2001, makna pembatasan hanya terlihat dalam Pasal 71 ayat (1) yang mana disebutkan bahwa perjanjian lisensi tidak boleh memuat ketentuan, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan Invensi yang diberi Paten tersebut pada khususnya. Pasal tersebut tidak menjelaskan dengan tegas mengenai batasan-batasan seperti apa perjanjian lisensi yang merugikan perkonomian Indonesia atau pembatasan-pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam penguasaan dan pengembangan teknologi. Terhadap praktek persaingan tidak jujur yang mungkin terjadi akibat proses perjanjian lisensi paten, Indonesia memiliki Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sehingga apabila terjadi suatu pembatasan melalui tindakan, perjanjian dan posisi dominan yang mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam lisensi paten maka para pihak dapat dikenai ketentuan UU ini. b. Ditinjau dari Struktur hukum Terkait dengan adanya lisensi paten dalam kaitannya dengan alih teknologi, Direktorat Paten Direktorat Jenderal HaKI Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI merupakan instansi yang berwenang dalam menangani permasalahan mengenai lisensi Paten. Berbagai permasalahan timbul terkait pemberian lisensi paten ini diantaranya ialah mekanisme pendaftaran yang cenderung rumit dan panjangnya rantai birokrasi yang harus dijalani. Kondisi ini ditambah dengan masih kurangnya akses informasi secara online yang memudahkan para pihak yang ingin mendaftarkan suatu lisensi Paten. Di Indonesia, kerjasama diantara institusi-institusi yang berkaitan dengan paten belum berjalan maksimal. Seringkali terlihat masing-masing institusi lebih mengedepankan ego sektoral dalam menangani sejumlah permasalahan. Belum terlihat suatu koordinasi yang maksimal antara Kantor Paten di Indonesia dengan institusi-institusi lain seperti KPPU yang menangani permasalahan praktek monopoli. 160 ... c. Ditinjau dari Budaya Hukum Terkait dengan budaya hukum, tak dapat dilepaskan dari pengaruh masyarakat, karena suatu hukum merupakan sarana masyarakat dan bekerja di dalam masyarakat. Oleh karena itu suatu aturan hukum tidak dapat terlepas dari gagasan maupun pendapat-pendapat yang hidup dikalangan masyarakat. Masyarakat dapat menjadi penghambat sekaligus dapat memberikan sarana-sarana sosial dalam menerapkan sebuah aturan hukum. Dengan kata lain, efektifitas hukum dapat berjalan dimasyarakat kalau ada intervensi dari manusia. 24 Menyangkut HaKI memang timbul suatu permasalahan mendasar dikarenakan unsur filosofis HaKI ini sedikit banyak dipengaruhi oleh ideologi barat. Hal inilah yang mengakibatkan proses penegakan hukum HaKI di Indonesia cenderung stagnan. Dalam hal Paten, data Direktorat Jenderal HaKI memperlihatkan bahwa dari tahun 1991 hingga 2004, jumlah permohonan paten lebih banyak di ajukan oleh pihak asing. Dan secara persentase menguasai sebanyak 85% dari keseluruhan jumlah permohonan paten di Indonesia. 25 Kondisi yang mengindikasikan bahwa paten justru lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak asing. Terkait dengan pemberian lisensi paten, maka kecenderungan ini sedikit banyak akan mempengaruhi mekanisme perjanjian dalam pemberian lisensi paten. Apabila pihak asing itu berasal dari negara maju, maka kecendrungan ketidakseimbangan posisi tawar dengan pihak Indonesia sebagai negara berkembang riskan terjadi. Pada akhirnya, proses alih teknologi justru menyulitkan posisi Indonesia dan menjadikan ketergantungan yang semakin besar dan luas kepada pihak asing. Penutup Perjanjian dalam Lisensi Paten merupakan salah satu jenis perjanjian lisensi industrial yang umumnya diatur dalam hukum Perdata. Dengan demikian, perjanjian lisensi paten tidak berbeda dengan perjanjian perorangan lainnya. Hak-hak untuk menikmati dan menegakkan ketentuan-ketentuan lisensi bergantung pada sifat kontraktual lisensi tersebut. Pada Hakekatnya, perjanjian lisensi paten ini memberikan hak bagi penerima paten dari pemilik atau pemegang paten untuk melaksanakan patennya sesuai dengan klausul dalam perjanjian lisensi paten tersebut. Lisensi khususnya dalam paten merupakan salah satu cara pengalihan teknologi yang dapat dilakukan dan dimanfaatkan oleh negara berkembang dan terbelakang untuk dapat 24 Lawrence Friedman, 1975 The Legal System: A Social Science Perspective, Russell Sage Foundation, New York, hal. 81. 25 Insan Budi Maulana.op.cit, hal. 67. ... 161 menyesuaikan diri dengan proses globalisasi ekonomi yang disertai liberalisasi perdagangan. Dalam implementasinya, sejumlah permasalahan baik ditinjau dari substansi, struktur dan budaya hukum timbul akibat pelaksanaan perjanjian lisensi paten tersebut. Apabila permasalahan ini tidak dapat ditangani secara serius maka efektifitas pemberian lisensi paten bagi kepentingan alih teknologi di Indonesia menjadi tidak maksimal dan justru berpotensi merugikan Indonesia. Pemerintah sejalan dengan konsep negara welfare state , harus menyiapkan formulasi dan mekanisme yang jelas dalam hal pemberian Lisensi Paten. Harus terdapat aturan-aturan pelaksana yang tegas dan terperinci yang mengatur perlindungan hukum diantara pihak pemberi dan penerima lisensi agar misi alih teknologi melalui lisensi paten ini dapat tercapai. Karena kecenderungan lemahnya posisi tawar dari para pihak penerima lisensi, harus diperhatikan dengan seksama sejumlah persyaratan-persyaratan atau kewajiban-kewajiban tambahan dalam perjanjian lisensi paten. Ini wajib dilakukan untuk mewaspadai maksud dan tujuan dari pemilik atau pemegang paten untuk menciptakan suatu ketergantungan dari pihak penerima lisensi sehingga justru mengakibatkan tidak berjalannya proses alih teknologi. DAFTAR PUSTAKA Friedman, Lawrence,1975, The Legal System: A Social Science Perspective, Russell Sage Foundation, New York. Kartadjoemena, H.S, 1996, GATT dan WTO, Sistem Forum dan Lembaga Internasional Di Bidang Perdagangan, UI-Press, Jakarta. Maulana, Insan Budi,1996, Lisensi Paten, Citra Aditya Bakti, Bandung. Saidin, OK, 2003, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Simatupang, Richard Burton, 2003, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta. Widjaya, Gunawan, 2001, Seri Hukum Bisnis Lisensi, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Yayasan Klinik HaKI, 1999, Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten dan Merek dan Terjemahan Konvensi-Konvensi di Bidang HaKI, Citra Aditya Bakti, Bandung. ... 162 STANDARISASI DAN KONSEKUENSI HUKUM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM INDUSTRI PARIWISATA BALI Ni Putu Yogi Paramitha Dewi Ombudsman Republik Indonesia [email protected] Abstract: A concept of Corporate Social Responsibility (CSR) has become a new mantra in corporate world recently. The concept embraces that corporations have a moral and ethical responsibility in contributing to economic development, social justice and environmental protection. However, the concept itself remains debatable in the context of business law due to competing interests between the proponent of regulated corporate behavior and the advocates of deregulation. In examining the standard of CSR in Indonesia as well as analysing the legal consequences of Article 74 of the 2007 Indonesian Company Act on the obligation to undertake CSR, this study has been conducted based on non-probability methodology, namely purposive and snowball sampling. The scope of the study is confined to hotels with limited company legal nature in Bali. The study shows that the standard of CSR in Indonesia remains inconclusive. Furthermore, if a company fails to comply with its obligation to undertake CSR, the Company Act refers to the specific laws under which the company oparates. In the context of this study, the lex specialis is the 2009 Indonesia Tourism Act. In order to implement CSR effectively, it is required a more applicable and clearer regulation on CSR as well as institutional arrangements to monitor and supervise the implementation of such regulation. Key words: corporate social responsibility (CSR), limited company (Ltd.co), hotel company Pendahuluan Sejak 2007 telah terjadi perubahan yuridis yang cukup signifikan dalam menentukan politik hukum dan praktek perseroan terbatas (PT) di Indonesia. Hal ini merupakan akibat dari dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 26 yang selanjutnya disingkat menjadi UUPT dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM) 27. Kelahiran kedua UndangUndang tersebut mampu membawa konsep Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi bagian penting dalam praktek bisnis korporasi. Alhasil, konsep CSR menjadi sangat populer khususnya di sektor usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam, misalnya pertambangan. Namun, konsep ini sendiri belum begitu populer terutama di dunia perhotelan yang disebabkan oleh beberapa faktor misalnya, kurangnya pemahaman tentang CSR serta perbedaan dalam penggunaan istilah untuk menyebut tanggung jawab sosial perusahaan. Dari penelitian yang dilakukan terhadap 6 hotel yang ada di Bali, meskipun mereka masih awam dengan istilah CSR, sejatinya 26 27 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724 ... 163 kegiatan-kegiatan yang serupa mereka lakukan dengan beberapa nama seperti community development dan green action. Selain faktor diatas, masih terdapatnya perbedaan tafsir terhadap UUPT terkait standarisasi dan konsekuensi hukum bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban CSR-nya, menyebabkan menyebabkan usaha jasa perhotelan di Bali bersifat menunggu aturan yang lebih jelas. Berdasarkan pendahuluan diatas, maka tulisan ini dibuat untuk coba mengkaji standarisasi pelaksanaan CSR terhadap perusahaan (PT) yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam, khususnya yang bergerak di bidang usaha perhotelan dan melakukan analisis terhadap akibat hukum yang ditimbulkan apabila hotel tersebut tidak melaksanakan CSR. Sejarah dan Perkembangan CSR CSR merupakan sebuah konsep yang sampai hari ini masih menjadi bahan pembicaraan di kalangan akademis maupun di dunia bisnis. Hal ini tidak terlepas dari adanya perbedaan pandangan antara para penganut teori ekonomi klasik sebangsa Adam Smith yang menyatakan bahwa tugas korporasi diletakkan semata-mata mencari keuntungan, “the only duty of the corporation is to make profit”. 28 Pandangan ini juga selanjutnya dianut oleh Milton Friedman, bapak dari Neo-Liberalisme. Pada tahun 1962, Milton Friedman dalam bukunya yang berjudul: Capitalism and Freedom dan salah satu tulisannya yang termuat dalam The New York Times Magazine pada intinya berpendapat bahwa jikalau pun sebuah perusahaan melakukan kegiatan sosial, hal ini bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan dan kekayaan perusahaan bagi para pemegang sahamnya 29. Berawal dari pendapat Friedman inilah akhirnya banyak perusahaan yang bersikap anti sosial dan cenderung melakukan praktik yang eksploitatif terhadap pekerja dan lingkungan hidup. Dalam perkembangannya, banyak reaksi bermunculan dalam merespon praktekpraktek korporasi yang eksploitatf tersebut. Misalnya komunitas internasional mulai mendorong penghormatan dan pelindungan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) dalam operasi korporasi. Selain itu, sejak beberapa tahun terakhir ini organisasi-organisasi internasional ataupun di banyak negara juga memberikan perhatian pada tanggung jawab korporasi dan menerapkan Corporate Social Responsibility dengan tujuan sebagai kompetitif 28 Sofyan Djalil, Kontek Teoritis dan Praktis Corporate Social Responsibility, Jurnal Reformasi Ekonomi Vol.4. No.1 Januari-Desember 2003, hal. .4. 29 Milton Friedman, 1970, “The Social responsibility of Business is to Increase its Profits”, The New York Times Magazine, http://www.colorado.edu/studentgroups/libertarians/issues/ friedman, diakses tanggal 5 Agustus 2011, hal. 1. ... 164 advantage. Beberapa usaha yang juga dilakukan oleh komunitas internasional dalam rangka mencoba untuk mendamaikan kepentingan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memenuhi keadilan sosial, diantaranya pertemuan internasional KTT Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992 tentang pembangunan berkelanjutan, pertemuan internasional Johannesburg pada tahun 2002 yang dihadiri para pemimpin dunia memunculkan konsep social responsibility, dan dilanjutkan pada 7 Juli 2007 di Jenewa, Swiss, dalam sebuah pertemuan bertema United Nations (UN) Global Compact. Terobosan besar dalam konteks CSR kemudian dilakukan oleh John Elkington melalui konsep "3P" (Profit, people, and planet). Konsep ini dituangkan dalam bukunya "Cannibals with Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business" yang dirilis pada tahun 1997 sebagaimana dikutip oleh Wayne Visser, et.al. 30 la berpendapat bahwa jika perusahaan ingin operasionalnya berlanjut (sustain), maka ia perlu memperhatikan 3P diatas. Jadi, perusahaan tersebut tidak bisa, hanya memburu profit semata, namun ia juga harus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat (people), dan ikut aktif dalam menjaga lingkungan hidup (planet). Mengenai definisi corporate social responsibility memang saat ini masih dalam perdebatan. Misalnya, Uni Eropa, lembaga perhimpunan negara-negara di benua Eropa, mencoba mendefinisikan CSR sebagai berikut: "CSR is a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basic". Selain rumusan tersebut diatas, Michael Hopkins 31 menyatakan bahwa: “CSR is concerned with treating the stakeholders of the firm etchically or in a responsible manner. ‘Ethically or responsible’ means treating stakeholders in a manner deemed acceptable in civilized societies. Social includes economic responsibility, stakeholders exist both within a firm and outside. The natural environment is a stakeholder. The wider aim of social responsibility is to create higher standards of living, while preservinmg the profitability of the corporation, for people both within and outside the corporation”. Dari dua rumusan definsi diatas, dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini belum ada kesamaan bahasa dalam merumuskan dan memaknai CSR sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Pengertian yang diberikan oleh Uni Europa misalnya, dengan tegas menyatakan bahwa CSR didasari oleh kesukarelaan. Sedangkan disisi yang lain, Michael 30 Wayne Visser Et. al., 2010, The A-Z of Corporate Social Responsibility, John Wiley & Sons Ltd, UK, hal. 406. 31 Michel Hopkins, 2003, The Business Case For CSR: Where Are We?, International Journal for Business Performance Management, Vol. 5, No. 2, hal. 125. ... 165 Hopkins menggarisbawahi bahwa CSR merupakan tanggungjawab etis sehingga dapat diartikan sebagai sebuah kewajiban yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian apakah sebuah perusahaan bertindak etis atau tidak. Terlepas dari ketiadaan definisi baku tentang CSR, para peneliti membedakan CSR atas dasar pendekatan analisa yang dipakai. Beberapa pendekatan yang telah dikenal umum adalah pendekatan piramida oleh Archie Caroll dan pendekatan klasifikasi Lantos. Dalam makalahnya yang berjudul “The Boundaries of Strategic Corporate Social Responsibility (2001)”, Lantos mencoba mengkaji tulisan Caroll mengenai struktur piramida CSR, yang coba dia gambarkan pada tabel di bawah ini: 32 Tabel 1 Struktur Piramida CSR Archie Caroll (1979, 2000, 2001) Classification Lantos’ (2001) Corresponding Classification 1. Economic responsibilities: 1. Ethical CSR: be profitable for shareholders, morally mandatory fulfillment of a provide good jobs for employees, firm’s economic responsibilities, produce quality for customers. legal responsibilities, and ethical responsibilities. 2. Legal responsibilities: comply with laws and play by rules of 2. Altruistic CSR: the game. Fulfillment of an organization’s philanthropic responsibilities, going 3. Ethical responsibilities: beyond preventing possible harm conduct business morally, doing (ethical CSR) to helping alleviate what is right just and fair, and public welfare deficiencies, avoiding harm. regardless of whether or not this will benefit the business itself. 4. Philanthropic responsibilities: make voluntary contributions to society, 3. Strategic CSR: giving time and money to good Fulfilling those philanthropic works. responsibilities which will benefit the firm through positive publicity and goodwill. Sumber: Geoffrey P. Lantos Dengan menggunakan kerangka pendekatan seperti diatas, Lantos mencoba menjabarkan legitimasi CSR dalam tiga jenis, yaitu: etika, altruistik dan strategis. Pertama, Ethical CSR merupakan cara pandang bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan secara moral melampaui pemenuhan kewajiban perusahaan dari aspek ekonomi dan hukum, dan 32 Geoffrey P. Lantos, 2002, The Ethicality of Altruistic Corporate Social Responsibility, Journal of Consumer Marketing, Vol. 19, No. 3, hal. 206. ... 166 menjadi tanggung jawab etis perusahaan pula untuk sebisa mungkin menghindari konflik sosial. Oleh karena itu, sebuah perusahaan secara moral bertanggung jawab untuk setiap individu atau kelompok yang memiliki potensi menimbulkan konflik tertentu. Altruistic CSR memandang bahwa perusahaan mempraktekkan CSR dalam rangka membantu meringankan berbagai penyakit sosial dalam suatu komunitas atau masyarakat, seperti kurangnya dana yang cukup untuk institusi pendidikan, tidak memadainya anggaran untuk kesenian, pengangguran, masalah penyalahgunaan obat bius dan alkohol, serta mengentasan buta huruf. Justifikasi bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab altruistik untuk membantu masyarakat terletak pada kenyataan bahwa perusahaan memiliki kekuatan ekonomi dan sumber daya manusia yang besar sehingga dianggap mampu memberikan pengaruh positif bagi banyak pihak di luar perusahaan. Jadi, ada semacam kontrak sosial secara implisit antara perusahaan dan masyarakat, dimana perusahaan setuju untuk menjadi ‘pelayan’ yang baik bagi pengembangan masyarakat. Ketiga adalah Strategic CSR. Berbeda dengan dua model CSR diatas, Strategic CSR merupakan strategi perusahaan dengan jalan melibatkan layanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan strategis dari kegiatan usahanya. Di sini, perusahaan berkontribusi terhadap konstituen mereka (masyarakat), bukan hanya atas dasar kedermawanan perusahaan dan menjadi sesuatu yang baik untuk dilakukan, tapi juga karena mereka percaya kegiatan CSR akan menimbulkan dampak baik bagi kelangsungan usaha mereka dalam hal profit dan tanggung jawab mereka kepada para pemegang saham. Selanjutnya, penulis mengkaji standarisasi dan melakukan analisa hukum CSR dengan menggunakan kerangka pendekatan Lantos. Hal ini dilakukan dalam rangka mengklasifikasi praktek CSR oleh perusahaan jasa pariwisata, dalam hal ini hotel. Standarisasi dan Analisis Hukum CSR Saat ini banyak dikatakan bahwa Bali tengah menghadapi krisis lingkungan hidup yang sering kali dihubungkan dengan industri pariwisata yang ada. Menurut Walhi Daerah Bali, misalnya, hotel yang memiliki kolam renang dan lapangan golf di Bali memerlukan sedikitnya 3 juta liter air per hari sedangkan sebuah keluarga dalam satu rumah di Bali hanya memerlukan sedikitnya 200 liter air per hari 33, dan kamar hotel membutuhkan 2000 liter per hari per kamar 34. Belum lagi pengembangan pariwisata mewah di Bali telah mengakibatkan 33 Tourism Concern, 2009, “Golf”, http://www.tourismconcern.org.uk/golf.html, di akses pada tanggal 24 Oktober 2011. 34 Agung Wardana dkk, 2008, Bali Yang Rapuh: Lembar Informasi Lingkungan Hidup Bali 2008, WALHI Bali, Denpasar, hal. 50 ... 167 kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang cukup tinggi dan memaksa petani untuk menjual tanah mereka hingga tingkat konversi lahan mencapai 1000 hektar per tahun. 35 Lahan pertanian produktif di konversi ke tujuan non-pertanian termasuk hotel dan lapangan golf setiap tahunnya. 36 Menurut laporan dari Kementrian Lingkungan Hidup, Bali sejak tahun 1995 telah mengalami defisit air sebanyak 1,5 milyar m3 per tahun. Defisit tersebut terus meningkat di tahun 2000 hingga 7,5 milyar m3 per tahun 37, dan pada tahun 2015 mendatang, Bali diperkirakan akan mengalami defisit air sebanyak 27,6 milyar m3 per tahun. 38 Memang masih menjadi sebuah perdebatan apakah krisis lingkungan sebagaimana pembahasan diatas merupakan dampak langsung yang disebabkan oleh industri pariwisata di Bali. Oleh karena itu menjadi penting untuk mengklasifikasikan industri pariwisata sesuai dengan kategori yang diberikan oleh penjelasan Pasal 74 UUPT. Terdapat dua kategori kegiatan usaha yang diwajibkan melaksanakan CSR, yakni “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam”. Sedangkan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam”. Pengklasifikasian ini akan menentukan apakah usaha jasa perhotelan masuk dalam cakupan Pasal 74 UUPT yang wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun dalam konteks ekonomi-bisnis, usaha perhotelan dapat ditafsirkan bukan sebagai kegiatan usaha di bidang sumber daya alam karena perusahaan hotel tidak menjadikan sumber daya alam sebagai komoditas utama melainkan sebagai sarana pemuas pelayanan dan kenyamanan (leisure) kepada konsumen, yakni turis. Hal ini berbeda misalkan dengan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan yang merupakan usaha di bidang sumber daya alam karena jenis usaha ini menjadikan sumber daya alam sebagai komoditas untuk diperdagangkan. Selanjutnya, jika melihat dari konsumsi dan dampak jenis usaha perhotelan terhadap pemanfataan sumber daya air, maka penulis disini mengambil posisi bahwa jenis usaha perhotelan merupakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam. Hal ini dikarenakan bahwa Penjelasan Pasal 74 UUPT memberikan definisi kegiatan yang berkaitan 35 36 37 Loc.cit Ibid. Anonim, http://www.inwater.com/news/wmview.php?ArtID=900, diakses pada tanggal 24 Oktober 2011. 38 Ibid. ... 168 dengan sumber daya alam sebagai kegiatan usaha yang memiliki dampak terhadap fungsi sumber daya alam.Meski Pasal 74 UUPT mewajibkan jenis usaha ini untuk melaksanakan CSR, secara umum, hotel-hotel menafsirkan belum ada kewajiban hukum untuk melaksanakan CSR sampai adanya prosedur dan kriteria CSR yang jelas dan mengikat secara hukum. 39 Meski demikian, banyak hotel yang telah melaksanakannya secara sukarela dan bahkan menjadikan CSR sebagai nilai etis dalam operasional bisnisnya. 40 Sebagai sebuah kegiatan yang berdampak pada fungsi sumber daya alam, menurut penjelasan Pasal 74 UUPT, CSR wajib dilaksanakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang jasa perhotelan. Namun demikian, UUPT tidak menyebutkan dengan tegas akibat hukum yang timbul apabila sebuah hotel tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana di atas. UUPT hanya merujuk pada peraturan yang terkait dengan bidang usaha dari perusahaan dimaksud. Secara lex specialis, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (UU Kepariwisataan) merupakan peraturan terkait dengan usaha perhotelan dan Undang-Undang ini mewajibkan pelaku usaha pariwisata untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana termuat dalam Pasal 26 UU Kepariwisataan. Adapun bagi pelaku usaha pariwisata yang tidak melakukannya akan dapat berakibat pada penjatuhan sanksi administratif mulai dari teguran hingga penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana termuat dalam Pasal 63 Undang-Undang Kepariwisataan. Namun tidak dirinci lebih jauh prosedur dan kriteria penjatuhan sanksi tersebut dan institusi yang memiliki wewenang untuk itu. Dilihat dari sudut pandang hukum bisnis, setidaknya ada dua tanggung jawab yang harus dicermati dalam etika bisnis. Tanggung jawab tersebut yaitu tanggung jawab hukum (legal responsibility) yang meliputi aspek perdata (civil liability) dan aspek pidana (crime liability), dan aspek tanggung jawab sosial (social responsibility) yang dibangun di atas landasan norma moral yang berlaku di dalam masyarakat. 41 Artinya, sekalipun suatu kegiatan bisnis secara hukum (perdata dan pidana) tidak melanggar undang-undang atau peraturan, tetapi jika bisnis tersebut dilakukan dengan melanggar moral masyarakat atau merugikan masyarakat, maka kegiatan bisnis tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan tidak etis (unethical conduct). 39 Ni Putu Yogi Paramitha Dewi, 2012, “Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Terhadap Perusahaan (PT) Yang Bergerak Di Bidang Usaha Perhotelan (Studi Pada Hotel Berbentuk PT Di Bali)”, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hal. 102. 40 Ibid. 41 Ridwan Khaerandy, Corporate Social Responsibility: Dari Shareholder ke Stakeholder, dan Dari Etika Bisnis ke Norma Hukum, pada Workshop Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Yogyakarta 6-8 Mei 2008, hal. 9. ... 169 Peletakan kewajiban melaksanakan CSR bagi perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam sebagaimana tertuang dalam UUPT membawa konsekuensi hukum bagi perusahaan dan pemerintah. Bagi perusahaan yang bersangkutan pelaksanaan CSR menjadi keharusan yang tidak terelakan. Sedangkan bagi pemerintah ada kewajiban menegakkan aturan hukum tersebut kepada perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Selain itu, karena perbedaan tafsir yang terjadi di kalangan dunia bisnis, pemerintah sebaiknya menerbitkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan lebih lanjut dari tanggung Jawab sosial dan lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 74 UUPT. Secara prinsip regulasi CSR dalam UUPT memiliki landasan filosofi untuk menciptakan jalinan hubungan korporasi yang seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan nilai, norma, serta budaya masyarakat setempat. Sehingga dengan demikian perusahaan tidak hanya mengeksploitasi dan atau merubah fungsi dari sumber daya alam secara besar-besaran demi mengejar keuntungan ekonomi (minimize loss and maximize profits) saja tetapi juga memperhatikan tanggung jawab sosialnya. 42 Sesuai dengan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial untuk mengubah masyarakat, maka pengaturan CSR dalam UUPT menjadi relevan. Hal ini dikarenakan oleh kondisi hari ini dimana di tataran praktek banyak perusahaan yang hanya mengedepankan keuntungan ekonomis tanpa memperdulikan dampak sosial dan lingkungan yang diakibatkan oleh aktifitas perusahaan-perusahaan tersebut. Sebagai contoh untuk perusahaan yang bergerak di bidang jasa pariwisata terutama yang berbentuk hotel, program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan di sekitar hotel merupakan kewajiban rutin perusahaan karena sejak berdiri sampai beroperasi, hotel tersebut memiliki kontribusi besar terhadap perubahan fungsi lingkungan hidup dan budaya setempat. Melalui teori keberlakuan hukum Lawrence M. Friedman, disebutkan 3 elemen dalam menilai efektivitas sebuah penegakan hukum. Pertama, mengenai substansi hukum, substansi hukum terdiri dari norma-norma hukum esensial, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat terkait dengan adanya Pasal 74 UUPT, organisasi atau institusi. Kedua, struktur hukum, merupakan bentuk nyata dari sebuah sistem hukum yang memungkinkan pelayanan dan penegakan hukum dimana kelembagaan yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kegiatan perusahaan yang dalam hal ini perhotelan di dalam melaksanakan praktik CSR belum terbentuk dan harus dibentuk. Ketiga, budaya hukum, berupa ide-ide, sikap, harapan, 42 Arif Budimantana, Adi Prasetijo, dan Bambang Rudito, 2008, Corporate Sosial Responsibility: Alternatif Bagi Pembangunan di Indonesia, ICSD, Jakarta , hal. 23. ... 170 pendapat dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum (positif atau negatif) 43 perlu dilakukan sosialisasi mengenai adanya peraturan yang dalam hal ini UUPT yang mengatur ketentuan mengenai CSR di dalamnya untuk dapat lebih di gunakan sebagai acuan bagi pelaku usaha perhotelan. Penutup Standarisasi CSR bagi perusahaan (PT) sampai saat ini belum diatur secara jelas. Namun ketidakjelasan ini memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yakni dapat memberikan kebebasan bagi perusahaan untuk memilih bentuk CSR sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari perusahaan tersebut. Sedangkan negatifnya yaitu dari sisi penegakan hukum, ketidakjelasan standarisasi yang berdampak juga pada kriteria CSR menimbulkan kesulitan bagi pembuat dan pelaksana kebijakan untuk menilai apakah CSR yang dilakukan oleh perusahaan telah mencapai tujuan yang diharapkan oleh Pasal 74 UUPT. Sehingga perlu adanya kesatuan pengaturan terkait Corporate Social Responsibility (CSR) di tingkat internasional dan nasional memperjelas pengaturan di tingkat nasional khususnya Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah dan pembuat undang-undang agar kewajiban dan hak dari pelaku usaha terhadap stakeholder terperinci dengan jelas. Pengaturan yang perlu diperjelas yaitu memuat subyek Corporate Social Responsibility yang tidak hanya perusahaan dalam bidang sumber daya alam akan tetapi seluruh bidang perusahaan, termasuk di dalamnya usaha jasa perhotelan. Khusus untuk sektor pariwisata, perlu adanya sosialisasi Global Code of Ethics for Tourism yang bisa digunakan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan kode etik dalam menjalankan CSR. Akibat hukum yang timbul apabila perusahaan tidak melaksanakan CSR berupa penjatuhan sanksi yang merujuk pada peraturan perundangan-undangan terkait dengan bidang usaha yang dilakukan. Jika dalam hal usaha jasa perhotelan, maka perturan terkait yang dimaksud adalah UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan yang mana mewajibkan pelaku usaha jasa pariwisata melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup. Pelanggaran terhadap kewajiban ini berkonsekuensi kepada dapat dijatuhkannya sanksi administratif mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha hingga pembekuan sementara jenis usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang43 Lawrence Meir Friedman, 1987, Legal System: a Social Science Perspective, http://books.google.com/books?id=DKJ654VkMb8C&pg=PA15&lpg=PA15&dq=legal+substance+structure+ culture&source=bl&ots=BpbwjyFDCP&sig=0csopdjzVUTVgcsuHp9viwgw1XI&hl=en&ei=z0rZSuvH6KI0wTkzulN&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CBIQ6AEwAg#v=onepage&q=legal %20substance%20structure%20culture&f=false, diakses pada tanggal 24 Oktober 2011 ... 171 Undang Kepariwisataan. Prosedur penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud diatas dibutuhkan penjabaran lebih jauh lewat peraturan pelaksanaan namun hingga saat ini aturan tersebut belum juga dikeluarkan oleh pemerintah secara tertulis. Mengingat Pasal 74 UU PT hanya mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan secara umum dan mendelegasikan peraturan pelaksanaannya pada peraturan pemerintah (PP), maka untuk menciptakan kepastian hukum, PP tersebut harus segera terbentuk sebagai pedoman pelaksanaan bagi perseroan yang terkena kewajiban melaksanakan CSR. Selain itu, juga dibutuhkan mekanisme pengawasan CSR dalam sektor pariwisata. Mekanisme ini juga termasuk pembentukan institusi atau badan pengawas baik dalam payung kelembagaan pemerintah (Kemenbudpar atau Dinas Pariwisata Daerah) atau di internal asosiasi pengusaha perhotelan atau dapat juga melalui mekanisme komplain publik dimana masyarakat dapat melaporkan secara langsung kepada dinas atau kementrian atau institusi yang berwenang apabila menemukan perusahaan yang melanggar kewajiban sosial dan lingkungannya. DAFTAR PUSTAKA BUKU Aguilera, William Cynthia, 2006, Corporate Social Responsibility in a Comparative Perspective, College of Law University of Illinois. Bantekas, Illias, 2004, Corporate Social Responsibility in International Law, 22 Boston University International Law Review. Branson, Douglas M., 2001, “Corporate Governance “Reform” and the New Corporate Social Responsibility”, 62 University of Pittsburgh Law Review 605 Budimantana, Arif, Adi Prasetijo, dan Bambang Rudito, 2008, Corporate Sosial Responsibility: Alternatif Bagi Pembangunan di Indonesia, ICSD, Jakarta. Cheeseman, Henry R., 2000 Contemporary Business Law, Third Edition, Prentice Hall, New Jersey Conill, Jesus, et.al., 2008, Corporate Citizenshi, Contractarianism and Ethical Theory: On Philosopical Foundations of Business Ethics, Ashgate Publishing Limited, England. Gjolberg, Maria & Audun Ruud, 2005, Working Paper: The UN Global Compact- A Contribution to Sustainable Development?, Centre for Development and the Environment University of Oslo. Goel, Ran, 2005, Guide to Instruments of Corporate Social responsibility: An Overview of 16 key Tools For Labour Fund Trustesss, Schulich, Canada’s Global Business School, University of Toronto, Canada. Hidayat, Syarif., 2008, Pengaruh Globalisasi Ekonomi dan Hukum Ekonomi Internasional Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. ... 172 Susanto, A.B., 2007, Corporate Social Responsibility: A Strategic Management Approach, The Jakarta Consulting Group, Jakarta. Vellas, Francois dan Lionel Becherel, 2008, Pemasaran Pariwisata Internasional: Sebuah Pendekatan Strategis, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta Visser, Wayne, 2010, The A-Z of Corporate Social Responsibility, John Wiley & Sons Ltd., United Kingdom Wardana, Agung, dkk, 2008, Bali Yang Rapuh: Lembar Informasi Lingkungan Hidup Bali 2008, WALHI Bali, Denpasar. JURNAL Carrol, Archie B., 1999, Corporate Social Responsibility: Evolution of a Defitional Contructs, Bisnis and Society, Vol. 13 No. 3 Carrol, Archie B., & Mark Schwartz, 2003, Corporate Social Responsibility: a Three Domain Approach, Bisnis Ethics Quarterly, Vol. 13 Cecill, Lianna, 2010, Corporate Social Responsibility in the United States, McNair Scholar Research Journal, Vol. 1 Frynes, Jedrsej G., 2008, Corporate Social Responsibility and International Development: Critical Assessment, Blackwell Publishing, Vol. 16 No. 4 Hopkins, Michael, 2003, The Business Case For CSR: Where Are We?, International Journal for Business Performance Management, Vol. 5, No. 2 Jennifer A. Zerk, 2006, Multinationals and Corporate Social Responsibility: Limitations and Opportunities in International Law, Cambrige University Press, UK Lantos, Geoffrey P., 2002, The Ethicality of Altruistic Corporate Social Responsibility, Journal of Consumer Marketing, Vol. 19, No. 3 _________________, 2002, The Ethicality of Altruistic Corporate Social Responsibility, Journal of Consumer Marketing, Vol. 19 No. 3 Rosser, Andrew & Edwin, Donni, 2010, The Politics of Corporate Social Responsibility in Indonesia, The Pacific Review, Vol. 23 No. 1 Williams, Oliver F., 2004, The UN Global Compact: The Challenge and The Promise, Business Ethics Quarterly, Volume 14, Issue 4 INTERNET Anonim, 2010, “Memahami Corporate Social Responsibility Sebagai wujud Investasi Perusahaan”, www.google.com/peranancsr, diakses pada 24 Oktober 2011. Baker, Mallen, 2004, “Corporate Social Responsibility: What Does It mean?, News and Resources”, www.mallenbaker.net, diakses pada 24 Oktober 2011. Caroll, Archie B., 1999, “Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct, Business and Society”, http://bas.sagepub.com/, diakses pada 24 Oktober 2011. Friedman, Milton, 1970, “The Social responsibility of Business is to Increase its Profits, The New York Times Magazine”, ... http://www.colorado.edu/studentgroups/libertarians/issues/ pada 24 Oktober 2011. friedman, 173 diakses Friedman, M. Lawrence, 1987, “Legal System: a Social Science Perspective”, http://books.google.com/books?id=DKJ654VkMb8C&pg=PA15&lpg=PA15&dq =legal+substance+structure+culture&source=bl&ots=BpbwjyFDCP&sig=0csopdj zVUTVgcsuHp9viwgw1XI&hl=en&ei=z0rZSuvH6KI0wTkzulN&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CBIQ6 AEwAg#v=onepage&q=legal%20substance%20structure%20culture&f=false, diakses pada 24 Oktober 2011. ... 174 THE KYOTO PROTOCOL’S DILLEMMA: AN ASSESSMENT OF THE FLEXIBLE MECHANISMS IN ADDRESSING CLIMATE CHANGE Agung Wardana Faculty of Law, Undiknas University [email protected] Abstrak: Perubahan iklim telah menjadi masalah lingkungan terbesar yang dihadapi umat manusia. Masyarakat internasional telah meresponnya dengan mengeluarkan Protokol Kyoto, yang menyediakan tiga mekanisme fleksibel untuk membantu negara-negara maju memenuhi komitmen mereka dalam mengurangi emisi gas rumah kaca yang menjadi penyebab utama perubahan iklim. Mekanisme fleksibel, yang didasarkan pada pasar dan skema pengaturan, Protokol ini tidak efektif dalam menanggulangi akar penyebab perubahan iklim. Namun, itu tidak berarti bahwa Protokol Kyoto, secara umum, telah gagal dan harus diganti dengan kesepakatan baru. Mengingat konteks politik saat ini di tingkat internasional, sebuah usaha untuk mengakhiri Protokol Kyoto dapat membahayakan negosiasi iklim karena seluruh perjanjian baru akan tidak mengikat secara hukum dan tanpa target pengurangan emisi global. Oleh karena itu, proyek ini menunjukkan bahwa perbaikan kelemahan Protokol Kyoto justru yang diperlukan, dan ini menjadi solusi yang paling layak untuk mengurangi emisi di masa depan. Kata Kunci: Perubahan Iklim, Hukum Internasional dan Protokol Kyoto. Introduction For decades, the issue of climate change has seemed to be one of the hottest political debates at both national and international levels. This has been argued through a wide range of writings across disciplines by many scholars. 44 For years, several skeptical groups [consisting of economists, corporate lobbyists and politicians] have appeared to argue that a report from the International Panel on Climate Change (IPCC) was not based on scientific evidence, but that it was based on political interest instead, and therefore climate change was not occurring. 45 In contrast, groups of scientists and environmental organizations tried to counter the skeptical arguments by campaigning the issue massively to inform the public. It seems that more open debates on climate change may have started since the IPCC, a global experts’ and scientists’ panel on climate change, released a report called the First Assessment Report in 1990. In the report, the IPCC provided scientific evidence on climate 44 See Zillman, N. D., ‘Preface: The Academic Advisory Group’ in Peter D. Cameron and Donald Zillman (eds), 2001, Kyoto: From Principles to Practice (Kluwer Law International, The Hague, xix; See also Bugge, HAL. Christian, ‘The Kyoto Protocol and the International Energy Industry: the Norwegian Perspective’ in Peter D. Cameron and Donald Zillman (eds) Kyoto: From Principles to Practice, Kluwer Law International, The Hague, p. 39. 45 Cameron, D. Peter, 2001, ‘The Kyoto Protocol Process: Past, Present and Future’ in Peter D. Cameron and Donald Zillman Kyoto: From Principles to Practice, Kluwer Law International, The Hague, p. 7. ... 175 change and its impacts for human life and the environment. In addition, IPCC recommended that an international legal instrument was needed in order to address climate change. 46 Therefore, in 1992, a convention named ‘United Nations Framework Convention on Climate Change’ (UNFCCC), the first international consensus on climate change, was released during the Earth Summit in Rio de Janeiro. The convention aims to stabilise the concentration of greenhouse gases “at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system” (Article 2 of the UNFCCC). Since it is a general framework, however, the convention does not provide a specific target on emissions reduction for its participating countries, so a protocol, which is a more specific legal instrument, was needed to implement the convention effectively. 47 Five years after the convention, the participating countries agreed to release the ‘Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change,’ otherwise known as the Kyoto Protocol, in 1997. As far as the international negotiations on climate change are concerned, the penetration of neo-liberalism with its free market principles seems to be influencing the processes as well as the Kyoto Protocol. 48 The most significant effort to involve the market in the Kyoto Protocol was the accommodation of three flexible mechanisms, namely Emissions Trading (ET), Joint Implementation (JI) and the Clean Development Mechanism (CDM), to solve the climate problems. These mechanisms have been the central debates on how effective the Kyoto Protocol is. Therefore, this project aims to provide a discussion of the effectiveness of the Kyoto Protocol’s flexible mechanisms in reducing greenhouse gas emissions in developed countries, and to propose possible solutions for the Kyoto Protocol’s dilemma. The Kyoto Protocol’s Mechanisms The flexible mechanisms have been accommodated in the Kyoto Protocol in order to provide flexibility for developed countries to meet their commitment in a cost-efficient manner. There are three flexible mechanisms. Firstly, Joint Implementation (JI) is a projectbased scheme between two developed countries to reduce emissions. The developed country 46 Grubb, Brack and Vrolijk, 1999, The Kyoto Protocol: A Guide and Assessment, Royal Institute of International Affairs, London,p. 5-7. 47 Peter Malanczuk, 1997, Akehurst’s Modern Introduction to International Law, 7th edn, Routledge, London, p. 52. 48 Grubb, Brack and Vrolijk (n 3) 137; Dabhi, Siddharta, ‘Where is Climate Justice in India’s First CDM Projects?’ in Bohm and Dabhi (eds), 2009, Upsetting the Offset: The Political Economy of Carbon Market, MayFlyBooks. London, p. 138-147; and Larry Lohmann, ‘Neoliberalism and the Calculable World: the Rise of Carbon Trading’ in Bohm and Dabhi (eds), 2009, Upsetting the Offset: The Political Economy of Carbon Market, MayFlyBooks, London, 2009, p. 25 ... 176 that funds the project will receive a credit called “emission reduction units” so that the country does not need to reduce its emissions domestically. Secondly, Emissions Trading (ET) is a scheme in which a developed country can buy allowances in releasing emissions, known as “Assigned Amount Units” (AAU), from another developed country. Finally, the Clean Development Mechanism (CDM), in principal, is the same with the JI; however, it is a partnership between a developed country and a developing country. As far as the effectiveness of a legal system is concerned, according to Friedman 49, there are three components that need to be assessed. Friedman names them as legal culture, legal substance, and legal structure 50. Firstly, the legal culture is related to paradigms and attitudes that shape “social forces” to obey or to disobey the rules. 51 Secondly, the legal substance consists of essential norms and laws on what should be done by organizations or institutions. 52 Thirdly, the legal structure is the physical form of a system, the institutions and the fixed foundations that maintain the system operating on its tracks. 53 Hence, the effectiveness of the flexible mechanisms in the Kyoto Protocol, as a part of an international legal system, is discussed based on Friedman’s categories in this section. With regard to legal culture, it seems that economic reasons, namely economic stability, growth and employment, have been the major argument in postponing taking actions on climate change. The US, for instance, has refused to ratify the Kyoto Protocol, although it was the architect of the flexible mechanisms. In addition, Australia had delayed its ratification until Kevin Rudd, who pledged to ratify the Kyoto Protocol during his campaign, was elected as the Prime Minister in 2007. It is a common argument that the Kyoto Protocol is ineffective because the US is not participating. The US, indeed, the biggest contributor of greenhouse gas emissions, produces approximately 25% of total global emissions and the highest per capita carbon footprint; thus, the international community projects the US as an indicator of success in reducing emissions at global level. 54 To some extent, it seems that the Kyoto Protocol, particularly the flexible mechanisms, may be seen as an ineffective legal instrument to tackle climate change. However, instead of being caused by the absence of the US, this ineffectiveness may be 49 Lawrence Friedman, 1987, The Legal System: a Social Science Perspective, Russell Sage Foundation, New York, p. 16 50 Lawrence Friedman (n 6) 51 Lawrence Friedman (n 6) 15 52 Lawrence Friedman (n 6) 14 53 Lawrence Friedman (n 6) 14 54 Grubb, Brack, and Vrolijk (n 3) 31 ... 177 caused by a paradigm of exploiting the issue of climate change in terms of economic selfinterest. This leads to failure in pursuing an effective answer to the issue as a top priority. Therefore, the legal culture, in terms of the counterproductive attitude and self-serving paradigm showed by participating countries, seems to influence the ineffectiveness of the Kyoto Protocol as an international legal system to address climate change. Driven by a neoliberal paradigm, the flexible mechanisms based on market and offsetting schemes have become the core of the Kyoto Protocol. They aim to provide economic opportunities instead of addressing the main causes of the problems effectively. Thus, debates on economic and environmental perspectives in these mechanisms seem to be important issues with regard to measuring the effectiveness of the substance of the Kyoto Protocol. From the economic point of view, it is frequently pointed out that the flexible mechanisms have positive impacts for both developed and developing countries. Most importantly, the mechanisms, argued by their proponents, are the cheapest solution to tackle climate change, particularly for developed countries 55. For developing countries, the mechanisms, primarily the Clean Development Mechanism (CDM), provide opportunities and economic advantages in addressing climate change. 56 This means that the flexible mechanisms may be as delaying schemes for developed countries from reducing their emissions domestically, and as fundraising schemes for developing countries. However, from the environmental perspective, particularly to reduce emissions, the flexible mechanisms do not appear to solve the root causes of the climate problems. The impacts of the CDM in reducing emissions, for instance, according to the U.S General Accountability Office (GAO), is difficult to calculate precisely. 57 Moreover, the Institute for Applied Ecology cited in Melisa Checker reports that 49 % of the CDM projects registered up to 2007 were doubtful to have reduced emissions 58. Hence, although the developed countries may hold CER credits from CDM projects, there were no emissions that have been reduced from the projects. The same problems also occur in the two other mechanisms, such as Emissions Trading and Joint Implementation. According to Rising Tide, a US based grassroots 55 Böhm, and Dabhi, ‘Upsetting the Offset: An Introduction’ in Bohm and Dabhi (eds), 2009, Upsetting the Offset: The Political Economy of Carbon Market, MayFlyBooks, London, p. 14. 56 David Victor, 2001, The Collapse of the Kyoto Protocol and the Struggle to Slow Global Warming, Princeton University Press, Princeton, p. 7. 57 Melissa Checker, ‘Double Jeopardy: Pursuing the Path of Carbon Offsets and Human Rights Abuses’ in Bohm and Dabhi, 2009, Upsetting the Offset: The Political Economy of Carbon Market, MayFlyBooks, London, p. 44. 58 Melissa Checker (n 14) ... 178 environmental organisation, the emission-trading mechanism in the European Union, the European Emissions Trading Scheme (EU-ETS), has failed due to “fraud and market manipulation”. Nearly half of all the spots traded for the scheme are “unsatisfactorily monitored”. 59 With regard to the European Union, the European Commission claims that they reduced 3.6 % emissions below 1990 levels between 2007-2008 using about 1,500 CDM projects. However, new research conducted by Michael Wara, a law professor at Stanford University, reports that European Countries increased their emissions approximately 1 % above 1990 levels in 2008 60. According to the Subsidiary Body for Implementation (SBI) of the UNFCCC, the emissions from Annex 1 Countries [developed countries] increased by 3.1 % from 2000 to 2007. 61 This implies that the flexible mechanisms provided by the Kyoto Protocol seem to be ineffective in meeting the aim of the UNFCCC and the Kyoto Protocol in stabilizing the earth’s temperature. Since 2000, when the first flexible mechanism was implemented, there were no significant reductions in emissions. Indeed, greenhouse gas emissions have continued to increase. With respect to institutions on the flexible mechanisms, the most crucial to be assessed is the CDM Board. In addition, the enforcing body of the Kyoto Protocol, the Enforcement Branch, also plays an important role in ensuring the aims of the UNFCCC and the Kyoto Protocol are accomplished. Thus, in this section, the CDM Board and the Enforcement Branch under the Kyoto Protocol are discussed in order to assess their effectiveness. As far as enforcement is concerned, the Enforcement Branch may be the main body to ensure whether the developed countries reach their commitment. In addition, the Branch also regulates the flexible mechanisms in terms of eligibility to implement the mechanisms. 62 However, these functions seem difficult to apply for various reasons. Maljean-Dubois argues that the market-based mechanisms would depend on the market and not the Branch’s decision. 63 In addition, the members of the Enforcement Branch may tend to be unprofessional because they represent strong political and economic interests from their home 59 Rising Tide North America, Hoodwinked in the Hothouse: False Solution to Climate Change (Rising Tide North America, Oakland, n.d), p. 9 60 Melissa Checker (n 14), p. 44 61 Subsidiary Body for Implementation, “National Greenhouse Gas Inventory Data for Period 19902007”, (UNFCCC, Bonn, 2009) <http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/3594.php?rec=j&priref=600005460#beg> [14 May 2010] 62 Depledge and Yamin, 2004, The International Climate Regime: A Guide to Rules, Institutions and Procedures, Cambridge University Press, Cambridge, p. 393. 63 Sandrine Maljean-Dubois, ‘An Outlook for the Non-Compliance Mechanism of the Kyoto Protocol on Climate Change’ (2010) 2 Amsterdam Law Forum Journal, p. 79 ... 179 countries or groups 64. Moreover, members of the Branch who are coming from poor countries may face difficulties in forcing the rich and powerful countries to meet their commitments. 65 In terms of the role of the CDM Board, Wara and Victor argue that the Board has no adequate data or information on every single CDM project, and the Board is also pressed by both developed and developing countries to approve their projects. 66 Additionally, a project proponent requires hiring CDM validators during the project assessment; as a result, the validators may face a conflict of interest in making an objective decision. 67 Therefore, the structure of the Kyoto Protocol Mechanism appears to be ineffective due to the lack of professionalism, data and procedures, different interests of the participating countries, and aid-dependency of poor countries on rich countries. Between Terminating and Improving the Kyoto Protocol In spite of being the cheapest way to address climate change, the flexible mechanisms seem to create new problems by providing a delaying scheme to tackle the root causes of climate change. Thus, possible solutions are needed that are more effective to regulate the participating countries’ ability to take actions on adaptation and mitigation of the impacts of climate change. Currently, there are two main proposals at the international level in response to the ineffectiveness of the Kyoto Protocol. The first proposal has been promoted by several groups, namely the US, academic institutions, and corporate lobbyists saying that a new agreement is needed. In the fifteenth Conference of Parties (COP 15) in Copenhagen in 2009, the US tried to terminate the UNFCCC and the Kyoto Protocol in order to propose a new treaty. Using its economic and political power, the US pushed developing countries to agree with this proposal. On the other hand, the other developed countries, including Germany and the United Kingdom, pushed China and India to reduce their emissions due to the absence of the US in the Kyoto Protocol, even though they are developing countries. 68 64 T. Kolari (2006) ‘International Environmental Treaties and State Behavior: Factors Influencing Cooperation & Implementing the Climate Regime, International Compliance (Book Review)’ (2006) 17 European Journal of International Law, p. 877. 65 A. Agarwal, 2002 ‘A Southern Perspective on Curbing Global Climate Change’ in Schneider, and others (eds) Climate Change Policy: A Survey, Island Press. Washington, p. 382 66 Gilbertson and Reyes, 2009, Carbon Trading: How it Works and Why it Fails, Dag Hammarskjold Foundation, Uppsala, p. 64. 67 Barbara Haya, 2007Failed Mechanism: How the CDM is Subsidizing Hydro Developers and Harming the Kyoto Protocol, International Rivers, Berkeley, p. 10. 68 Lim Li Lin, ‘Kyoto Protocol Work Continues in 2010 Despite Threats to its Future’ (2010) TWN Bonn Climate Change Update No.5 <http://www.twnside.org.sg/title2/climate/bonn.news.5.htm> accessed 5 May 2010. ... 180 The second proposal is to improve the weaknesses of the Kyoto Protocol instead of terminating it. This proposal has been endorsed by the major groups of developed countries as well as developing countries, environmentalists, and carbon-traders. However, they have different stances on what should be done to improve the Kyoto Protocol, whether strengthening the market-based and offsetting mechanisms or shifting these mechanisms into non-market and domestic based emissions reduction. As far as the collapse of the Kyoto Protocol is concerned, it seems clear that the best solution is not to terminate the UNFCCC and the Kyoto Protocol considering the legal status of the agreements and limited time to act. With regard to the legal status, the Kyoto Protocol is the only legally binding agreement on climate change at international level. Terminating the Kyoto Protocol would allow countries to emit greenhouse gasses into the atmosphere without any legally binding regulations. Although the proponents argue that they would promote a new agreement on climate change after terminating the Protocol, it seems that the new agreement would be voluntarily based instead of legally binding. This tendency can be seen in the Copenhagen Accord, the result of COP 15. In the Accord, there is neither a global emissions target nor binding commitment for developed countries. Therefore, it will not be sufficient to maintain the rise in temperature below 2 degree Celsius [the safest level estimated by IPCC]; in fact, it is predicted that emissions from developed countries will increase 10-20 %, meaning that the temperature will rise more than 3 degree Celsius in 2100 69. In terms of time frame, the impacts of climate change have been faced by several countries, particularly small island states and other developing countries 70. It seems that there is not enough time to negotiate a new climate change agreement since it would take time and postpone urgent actions that are needed. The Kyoto Protocol, for instance, took more than a decade, from 1992-2005, to be negotiated and entered into effect. Therefore, the new agreement may require even more time to put into force in light of the more complex debates on climate change, particularly concerning the current economic and political situation after a global financial crisis. This discussion could serve as a delaying tactic during the negotiation process. 69 Khor, Martin ‘Dire Warning by Scientists as Climate Talks Resume’ (2010) TWN in Bonn Update No.1 <http://www.twnside.org.sg/title2/climate/bonn.news.6.htm> accessed 31 May 2010; Rogelj, and others, ‘Copenhagen Accord Pledges Are Paltry’ (2010) 464 Nature: International Weekly Journal of Science 11261128 70 Friends of the Earth International, 2007, Voices from Communities Affected by Climate Change, FOEI, Amsterdam, p. 3. ... 181 It appears that the most possible solution may be to improve the Kyoto Protocol, particularly the flexible mechanisms. Instead of strengthening the market-based and offsetting mechanisms that have failed, the improvement of the legal substance of the Kyoto Protocol’s mechanisms may need to focus on non-market and domestic based emissions reduction schemes. Non-market and domestic-based schemes mean that developed countries may not sell or buy the “right to emit” from another country in order to meet their commitment by reducing emissions in their home countries. To avoid market involvement, financial support for this solution may come from a public fund to which developed countries can make contributions without any conditionality. In terms of the legal structure, the Enforcement Branch will need to be reformed in order to make it more robust and powerful. In addition, an “international environmental court”, as proposed by Malanczuk 71 seems to be an effective institution to complement the Branch in arbitrating the countries that do not fulfill a legal obligation. Moreover, a change in the legal culture, namely a paradigmatic shift from economic and political interest to climate justice principles, may be needed. Climate justice is a set of principles based on human rights and global justice perspectives in order to tackle climate change 72. In practice, the climate justice principles would require a “rapid phasing out of fossil fuel use” by halting the extraction of fossil fuel, demanding energy efficiency, acknowledging ecological debt and Indigenous People’s rights, promoting sustainable local farming and food sovereignty, and creating incentives through taxation 73. In addition, financial aid and technology transfers from developed countries to developing countries should be based on historical responsibilities from the Industrial Revolution when developed countries emitted large amounts of greenhouse gases into the atmosphere, now causing climate change. Moreover, unlike developing countries, developed countries have adequate resources to adapt and mitigate the impacts of climate change. Therefore, developed countries have to take a lead in addressing climate change, and helping developing countries to adapt and mitigate its impacts. In short, the improvement of the Kyoto Protocol’s mechanisms, namely non-market and non-offsetting based schemes, may be the most possible and safest solution in order to enforce the protocol in an effective manner. Furthermore, the future mechanisms should be 71 Peter Malanczuk (n 4), p. 52. International Climate Justice Network, <www.ejnet.org/ej/bali.pdf> accessed 27 May 2010 73 Gilbertson and Reyes (n 23), p. 92. 72 Bali Principles of Climate Justice (2002) ... 182 based on climate justice principles so that every country can stand equally in order to address climate change, the biggest environmental problem on earth. Conclusion The flexible mechanisms, namely Emission Trading, Joint Implementation and the Clean Development Mechanism, have been the central debate on the effectiveness of the Kyoto Protocol in reducing emissions in developed countries. As a part of an international legal system, these mechanisms have been assessed by using three components of the legal system: the structure, the substance and the culture, and to provide possible solutions for the future climate regime. Due to limited time and sources, this project has found that the Kyoto Protocol’s flexible mechanisms are ineffective in meeting the aims of the UNFCCC and the Kyoto Protocol to stabilise the earth’s temperature. Considering the attitude of participating countries, market-based solution, and the lack of an enforcement body, the mechanisms are far from solving the root causes of climate change. However, it does not mean that the Kyoto Protocol should be terminated because an attempt to do so may jeopardise general commitment to the issue of climate change. To terminate the Kyoto Protocol as promoted by the US would replace the legally binding commitment with a voluntary agreement since developed countries tend to seek more flexible ways in reducing emissions without legal and political sanctions. It seems that the best possible solution in responding the Kyoto Protocol’s dilemma is to improve its components with regard to non market-based and domestic emissions reduction schemes, to reform enforcement bodies and to promote climate justice principles. Therefore, more detail studies on how the components work will need to be conducted in order to tackle climate change effectively. BIBLIOGRAPHY BOOKS Bohm and Dabhi, 2009, the Offset: The Political Economy of Carbon Market, MayFlyBooks, London. Cameron and Zillman, 2001, Kyoto: From Principles to Practice, Kluwer Law International, The Hague. Depledge and Yamin, 2004, The International Climate Regime: A Guide to Rules, Institutions and Procedures,Cambridge University Press, Cambridge. Friends of the Earth International, 2007, Voices from Communities Affected by Climate Change, FOEI, Amsterdam. Gilbertson and Reyes, 2009, Carbon Trading: How it Works and Why it Fails, Dag Hammarskjold Foundation, Uppsala. ... 183 Grubb, Brack and Vrolijk, 1999, The Kyoto Protocol: A Guide and Assessment, Royal Institute of International Affairs, London. Haya, Barbara, 2007, Failed Mechanism: How the CDM is Subsidizing Hydro Developers and Harming the Kyoto Protocol, International Rivers, Berkeley. Malanczuk, Peter, 1997, Akehurst’s Modern Introduction to International Law, 7th edn. London: Routledge, London. Rising Tide North America, ---, Hoodwinked in the Hothouse: False Solution to Climate Change, the Rising Tide North America, Oakland, n.d. Schneider, Rosencranz and Niles, 2002, Climate Change Policy: A Survey, Island Press, Washington. Victor, G. David, 2001, The Collapse of the Kyoto Protocol and the Struggle to Slow Global Warming. Princeton: Princeton University Press, Princeton. JOURNALS Maljean-Dubois, Sandrine, ‘An Outlook for the Non-Compliance Mechanism of the Kyoto Protocol on Climate Change’ (2010) 2 Amsterdam Law Forum Journal 77-80 Rogelj and others ‘Copenhagen Accord Pledges Are Paltry’ (2010) 464 Nature: International Weekly Journal of Science 1126-1128 Kolari, T., ‘International Environmental Treaties and State Behavior. Factors Influencing Cooperation. & Implementing the Climate Regime, International Compliance (Book Review)’ (2006) 17 European Journal of International Law 874-879 INTERNET Friedman, M. Lawrence, “The Legal System: a Social Science Perspective (Russell Sage Foundation, New York, 1987)”, <http://books.google.com/books?id=DKJ654VkMb8C&pg=PA17&lpg=PA17&dq=f riedman+legal+system&source=bl&ots=BpbxiyFDCP&sig=p5oAKcC9eqAlHxfEAI VaOriXkAU&hl=en&ei=bwbnSOeHJey0gTx7aTUBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBkQ6 AEwAA#v=onepage&q&f=false> accessed 3 May 2010 International Climate Justice Network, “Bali Principles of Climate Justice”, 2002, <www.ejnet.org/ej/bali.pdf> accessed 27 May 2010 Khor, Martin, ‘Dire Warning by Scientists as Climate Talks Resume’, 2010, “TWN in Bonn Update No.1”, <http://www.twnside.org.sg/title2/climate/bonn.news.6.htm> accessed 31 May 2010 Lim Li Lin, ‘Kyoto Protocol Work Continues in 2010 Despite Threats to its Future’, 2010, “TWN Bonn Climate Change Update No.5”, <http://www.twnside.org.sg/title2/climate/bonn.news.5.htm> accessed 5 May 2010 UNFCC, “Subsidiary Body for Implementation, National Greenhouse Gas Inventory Data for Period 1990-2007 (UNFCCC, Bonn, 2009)”, <http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/3594.php?rec=j &priref=600005460#beg> accessed 14 May 2010 ... 184 PEMBUNUHAN DISERTAI MUTILASI DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI HUKUM I Made Badra Dinas Kebudayaan Provinsi Bali -----------Abstract: Crime mutilation usually occurs depends on the psychological of the perpetrator, where the actors tend to have psychiatric disorders. Mutilation crimes occur often done by people who are experiencing depression and psychiatric disorders, that the body is not cut up his victims, perpetrators are often not at all satisfied to solve crimes. To optimize the disclosure of a criminal act of mutilation murders will require collaboration with an investigator with the psychologist in the deep background or cause the perpetrator to commit the crime. The role of psychologists in penungkapan cases need to be optimized by way of tracing the involvement of psychologists in the mental condition of the offender. Psychologists are expected to provide expert opinion to investigators in connection with the case investigation. Key words: murder, mutilation, psychology of law. Pendahuluan Peristiwa pembunuhan maupun penganiayaan terus mengalami perkembangan yang diiringi dengan gaya dan model yang sangat beragam, dari cara yang paling sederhana sampai yang tercanggih. Terkadang pembunuhan itu dilakukan dengan cara-cara yang keji seperti disiksa lebih dahulu, dibakar dan bahkan mutilasi. Menjadi suatu fenomena karena mutilasi adalah pembunuhan yang diikuti dengan memotong-motong tubuh korban hingga menjadi beberapa bagian yang dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan bukti. Tindak kejahatan pembunuhan yang disertai mutilasi ternyata bukan hal baru di Indonesia, Pada tahun 1960-1970-an kejahatan pembunuhan disertai mutilasi ini sudah pernah terjadi. Adapun alasan pelaku melakukan mutilasi karena ingin menyembunyikan identitas korban supaya tidak diketahui orang lain, dan pelaku merasa puas setelah memutilasi korban. Sadis dan kejam, adalah sebutan yang pantas bagi para pelaku kejahatan pembunuhan disertai mutilasi. Setelah Robot Gedek dan Veri Idham alis Ryan dari Jombang sekarang ada Baekuni yang menghentakkan hukum di Indonesia akan sadis dan kejamnya pelaku mutilasi ini yang dengan tega dan sadar membunuh / menghilangkan nyawa orang lain, memutilasi korban bahkan melakukan kejahatan seksual terhadap anak laki-laki yang dibawah umur dan informasi terbaru pernah menculik anak perempuan selama 9 tahun. Sepanjang 2008, tercatat banyak kasus pembunuhan dengan cara mutilasi. Antara lain, kasus mutilasi dengan tersangka Verry Idham Henryansyah alias Ryan (34) di wilayah ... 185 hukum Polres Jakarta Selatan, dengan korban seorang laki-laki, Heri Santoso, yang dipotong tubuhnya menjadi tujuh bagian dan jasadnya dimasukkan ke dalam koper dan tas. Selain itu, yang terjadi pada 17 Januari 2008 dengan korban Atikah Setyani, wanita yang tengah hamil empat bulan yang dipenggal kekasihnya bernama Zaky di kamar Hotel Bulan Mas, Koja, Jakarta Utara. Lalu pada 17 Maret 2008. 74 Pembunuhan keji dan berantai dengan cara mutilasi yang dilakukan Baekuni alias Babe (48) menjadi berita ekstrim kali ini. Kekejian Babe mulai tercium saat ditemukannya potongan tubuh bocah di Cakung Jakarta Timur tanggal 8 Januari 2010. Aksi Babe diperkirakan sejak tahun 1998 dan pembunuhan cara mutilasi baru sejak tahun 2007. Ketujuh anak jalanan yang menjadi korbannya adalah Arif Kecil (6 tahun). Jasadnya ditemukan di terminal Pulogadung, tubuhnya dipotong jadi empat bagian. Waktu ditemukan Kamis 15 Mei 2008, dia dalam keadaan tanpa kepala. Dan Adi (12 tahun), Jasadnya ditemukan di Pasar Klender, Cakung, 9 Juli 2007. Tubuh korban dipotong menjadi dua bagian sebelum dibuang ke Pasar Klender. Kemudian Ardiansyah (10 tahun), Jasadnya ditemukan di Jalan Raya Bekasi KM 27, Ujung Menteng, Cakung, pada Jumat 8 Januari 2010. Pembunuhan dengan cara mutilasi selalu melibatkan sisi kondisi kejiwaan dari pelaku. Dapat dikatakan disini telah terjadi penyimpangan kondisi kejiwaan apalagi dalam banyak kasus mutalisasi, pelaku sama sekali merasakan kepuasan saat memotong-motong korban. Hal ini sangat menarik untuk membahas penelitian yang berjudul KONDISI PSIKOLOGIS PELAKU DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI MUTILASI. Kondisi Kejiwaan Pelaku Pembunuhan Disertai Mutilasi Kejahatan mutilasi biasanya terjadi tergantung kepada keadaan psikis si pelaku, dimana si pelaku cenderung mengalami gangguan kejiwaan, kejahatan memutilasi merupakan kejahatan susulan dari sebuah kejahatan pembunuhan, dengan maksud untuk menutupi kejahatan pembunuhan tersebut maka dilakukanlah pemutilasian tubuh korban, sehingga korban tidak diketahui keberadaannya ataupun jika diketahui maka akan menghambat penyidik untuk mengungkap identitasnya. Dari sisi ilmu kriminologi, secara definitive yang dimaksud dengan mutilasi adalah terpisahnya anggota tubuh yang satu dari anggota tubuh lainnya oleh sebab yang tidak wajar. Beberapa penyebab terjadinya mutilasi disebabkan oleh kecelakaan, bisa juga merupakan 74 Eko Hartanto, 2008, “Psikologi Forensik Kasus Mutilasi”, http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2008/07/31/24377/Psikologi.Forensik.Kasus.Mutilasi, diakses pada 3 Agustus 2011. ... 186 faktor kesengajaan atau motif untuk melakukan tindakan jahat (kriminal), dan bisa juga oleh faktor lain-lain seperti sunat. Sebagai suatu konteks tindak kejahatan biasanya pelaku melakukan tindakan mutilasi adalah dengan tujuan untuk membuat relasi antara dirinya dengan korban terputus dan agar jati diri korban tidak dikenali dengan alasan-alasan tertentu. Biasanya mutilasi dilakukan pelaku untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Selain itu, mutilasi juga dapat menjadi bentuk penyaluran amarah atau sakit hati yang lama terpendam. Kasus mutilasi dengan tujuan penghilangan jejak, umumnya akan lebih sulit untuk diungkap. Potongan tubuh korban akan ditemukan di tempat-tempat berbeda dengan jarak relatif berjauhan, juga tidak adanya identitas tertulis yang dapat ditemukan di tubuh korban. Dari beberapa kasus yang sudah terungkap, biasanya pelaku memiliki hubungan yang dekat dengan korban. Bisa juga karena ada pengaruh kehidupan keluarganya saat masih kecil. Cirinya pendiam, kalau ada masalah dipendam. Hanya pada suatu saat amarahnya meledak dan melampiaskannya dengan cara sendiri. Jadi, pada saat melakukan pembunuhan dan mutilasi itu, memang terjadi pada saat amarahnya meledak dan tidak dalam keadaan gangguan jiwa, dilakukan dalam kondisi normal, tidak menemukan gangguan psikologis. Kecemburuan juga dapat menjadi pendorong yang kuat, untuk melakukan tindakan mutilasi. Pada kasus pembunuhan karena cemburu yang disertai mutilasi, biasanya masih ada ketidakpuasan dari sang pelaku saat melihat pasangannya tewas. Mutilasi yang didasari rasa sakit hati, marah, dan kecemburuan, dimana tindakan menyakiti orang lain ini bertujuan untuk mencapai kepuasan pribadi. Aksi membunuh ternyata belum cukup meredakan amarah atau mengobati kekecewaan si pelaku. Pelaku yang sudah merasa tersakiti merasa bahwa kematian tidak cukup menyakitkan bagi sang korban maka diambillah keputusan untuk memotong-motong bagian tubuh. Motif tindakan mutilasi memang beragam, dari sekadar menghilangkan jejak, hingga melibatkan emosi yang mendalam, seperti kecemburuan, kekecewaan, dan kemarahan. Alasan-alasan dilakukannya tindakan mutilasi oleh pelaku terhadap korban tentunya dilatarbelakangi oleh motif-motif tertentu pula. pelaku menderita gangguan jiwa, sejenis sadism. Pelaku terpuaskan bila orang lain menderita, terbunuh, terpotong-potong. Ini bisa diketahui dengan hanya melihat potongan-potongan tubuh tersebut. Pada umumnya kalau motif yang dilatarbelakangi oleh motif cinta, potongannnya adalah di bagian-bagian genetalia seperti payudara, penis, dan yang lain. Namun kalau motifnya dendam, umumnya yang dimutilasi adalah bagian kepala. Kedua motif ini biasanya dilakukan dengan sengaja dan terencana yang disebabkan oleh rasa tidak puas pelaku mutilasi terhadap korban. ... 187 Kejahatan mutilasi sering sekali terjadi dilakukan oleh orang-orang yang memang mengalami depresi dan gangguan kejiwaan, bahwa dengan tidak memotong-motong tubuh korbannya, pelaku sering sekali tidak puas untuk menyelesaikan kejahatannya. Adapun motif utama pembunuhan mutilasi adalah menghilangkan identitas korban sehingga identitas korban sulit dilacak, apalagi pelakunya. Menghilangkan identitas dengan cara memotong-motong tubuh juga mencerminkan kepanikan pelaku. Usai melakukan pembunuhan, pelaku biasanya panik dan mencari jalan pintas untuk menyelamatkan diri. Pelaku pembunuhan mutilasi juga umumnya seseorang yang memiliki tingkat kecerdasan apalagi jika pelaku berpikir untuk menghilangkan kepala, jari, dan tulang adalah cara pelaku untuk mempersulit penyelidikan. Jika organ-organ penting untuk identifikasi hilang, uji DNA (deoxyribonucleic acid) menjadi satu-satunya cara. Tetapi itu bukan hal mudah, sebab uji DNA baru bisa dilakukan jika ada pembanding. Ada dua kemungkinan orang melakukan mutilasi. Pertama, pelaku khawatir dirinya akan ditangkap bila meninggalkan korbannya secara utuh. Mereka berpikir bila meninggalkan jejak, terungkapnya kasus tersebut akan sangat tinggi. Karena itu, untuk menghilangkan jejak, pelaku dengan sengaja melakukan mutilasi dengan harapan orang lain akan sulit mencari jejak korban maupun pelaku. Kedua, terlalu rapatnya beberapa kasus mutilasi yang terjadi akhir-akhir ini membuat para pelaku mengadopsi tayangan televisi atau media lainnya. Dengan demikian, para pelaku mengambil referensi dari berbagai ragam media massa,baik cetak maupun elektronik, yang tersebar di seluruh pelosok kota. Namun, kemungkinan yang paling besar adalah para pelaku panik dengan tindakan yang dilakukannya. Kemudian, mereka ingin aksi itu tidak diketahui banyak orang sehingga memutilasi korbannya. Kecenderungan anak yang menjadi korban kejahatan hingga pembunuhan adalah biasanya anak-anak yang tidak memiliki jaminan sosial seperti anak jalanan. Ada tiga aspek yang menyebabkan anak jalanan rentan menjadi korban kejahatan. Pertama, sebagian besar mereka tidak mendapatkan pengawasan yang baik dari orang tua mereka. Kedua, dorongan kondisi ekonomi yang memaksa mereka untuk bergantung pada orang lain. Ada ketergantungan kebutuhan ekonomi anak terhadap orang lain, karena tidak mereka peroleh dari orang tua, Sedangkan aspek ketiga adalah faktor lingkungan yang cenderung kurang peduli dengan kondisi yang menimpa anak-anak tersebut. Peristiwa pembunuhan dengan disertai mutilasi yang terjadi memang sering kali berhubungan dengan keadaan psikologi pelaku. Seperti kekejian oleh Babe yang mengidap ... 188 Pedofilia sehingga harus mengorbankan anak-anak untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Jadi semua lapisan masyarakat, institusi swasta dan pemerintah, aktifis dan pemerhati anak harus lebih serius bekerjasama dalam melawan dan memberi perlindungan kepada anak Indonesia dari ancaman segala kekerasan terutama pedofilia. Anak jalanan merupakan target para kaum pedofilia untuk memuaskan nafsunya. 75 Dalam pemeriksaan psikologi di Polda Metro Jaya, Babe mengaku telah melakukan pembunuhan berantai terhadap 7 bocah dan 4 diantaranya dimutilasi. Anak jalanan yang menjadi korban keganasan Babe rata-rata berusia 12 tahun ke bawah. Dari hasil pemeriksaan psikolog Universitas Indonesia (UI) Prof Sarlito Wirawan bahwa Babe mengidap homoseksual, pedofilia ataupun ketertarikan seksual dengan anak di bawah umur, dan nekrofil yaitu tertarik berhubungan seksual dengan mayat. Kelainan kejiwaan ini dilatarbelakangi oleh masa kecil Babe yang sering mendapat kekerasaan psikologis dan pernah di sodomi. Saat umur 12 tahun, Babe merantau ke Jakarta dan menjadi gelandangan di Lapangan Banteng. Di tempat itulah Babe pernah di sodomi. Babe kemudian dipungut seorang bernama Cuk Saputar dan dibawa ke Kuningan, Jawa Barat untuk menggembala kerbau. Ia dikawinkan saat umur 21 tahun, akan tetapi sejak dikawinkan dia nggak bisa ereksi, sampai istrinya meninggal. Setelah kejadian itu Babe kembali ke Jakarta berjualan rokok sambil mengasuh anak jalanan. Saat hasrat seksualnya datang, Babe mengambil orang di luar kelompoknya, yakni anak jalanan yang dibawa oleh anak-anak asuhnya. Sebelum membuang jasad korban, Babe menyetubuhinya lebih dulu dan kemudian memotong-motong tubuh korban. Waktu ditemukan, jasad korban dibungkus kardus. Empat bagian dibungkus kardus. Sedangkan kepala dibuang secara terpisah ke bawah jembatan, dekat lokasi penemuan tubuhnya. Selanjutnya Rio yang tubuhnya dipotong jadi empat bagian. Korban ditemukan warga di trotoar depan Bekasi Trade Center (BTC), Jalan Joyo Martono BTC Rt 3/21 Kelurahan Margahayu, Bekasi Timur, pada 14 Januari 2008. Riki juga ditemukan di terminal bus Pulogadung pada 2005. Dia dibunuh dengan cara dijerat lehernya lebih dulu ketika korban menolak disodomi. Setelah korban tidak berdaya, barulah disodomi. Setelah puas melampiaskan nafsu seks, korban dibunuh, dan mayatnya dibuang pakai kantong plastik. Selain itu Arif, mayatnya dibuang ke Kuningan, tepatnya di pinggir kali Kecamatan Ciwaru, Kuningan, Jawa Barat. Tubuh Arif tidak dimutilasi. Tapi dibunuh dengan cara dibenamkan kepalanya ke sungai. Kejadiannya 1999. 75 Anonim, “Baekuni (Babe) Pembunuh Keji Anak Jalanan”, http://ekstrimwebz.blogspot.com/2010/01/baekuni-babe-pembunuh-keji-anak-jalanan.html, , diakses pada 3 Agustus 2011. ... 189 Dia juga disodomi sebelum mayatnya dibuang. Dan Yusuf Maulana, ditemukan d halte Warung Jengkol, Kelapa Gading, pada 30 april 2007. Bocah ini usianya sekitar 9-12 tahun. Sama seperti Aris, tubuh Yusuf tidak dipotong-potong oleh Babe sebelum dibuang. Dalam kurun waktu tersebut terlihat adanya perubahan modus pelaku dari awalnya hanya membunuh dengan jerat di leher, menjadi mutilasi untuk menutup jejak. Apabila mengambil contoh kasus mutilasi yang dilakukan oleh Ryan. dengan bukti terakhir ditemukannya lima mayat oleh gabungan penyidik Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Timur baru-baru ini di rumah orang tuanya, menarik sekali kalau kita melihat dari kacamata psikologi forensik. Menurut pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel, pembunuhan berantai atau sadis (mutilasi), bagi pelakunya adalah untuk mendapatkan fantasi atau sensasi yang luar biasa dengan melihat korbannya meninggal atau detik-detik terakhir korban mengembuskan nafasnya (mati perlahan-lahan). Bila dikaitkan dengan ilmu psikologi forensik, kasus mutilasi dengan tersangka Ryan tidak ada kaitannya dengan orientasi seksual. Masyarakat awam dianggap terlalu berlebihan dalam menilai bila mengaitkan pelaku dengan homoseksual seorang Ryan. Psikopat, adalah sebutan dari masyarakat awam untuk pelaku mutilasi seperti Ryan itu. Dari segi fisik, memang sosok Ryan tidak terlihat psikopat, karena sikap/tingkah laku yang ditampilkannya di masyarakat menunjukkan pribadi yang santun, biasa, dan cerdas. Hal tersebut membuat masyarakat terkecoh. Tindakan sadis dengan mutilasi tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan untuk mencari tingkat fantasi yang maksimal (terpuaskan). Kalau merasa belum puas dengan tindakannya, pelaku akan mencari cara yang lebih sadis dan spektakuler (canggih). Memang, kalau berbicara masalah faktor penyebab pelaku melakukan tindakan abnormal tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor lain; di antaranya faktor pemicu (terjadinya sesaat, sebelum mutilasi tersebut dilakukan) dan faktor trauma yang mendalam atau peristiwa luar biasa (kekerasan) yang dialami pelaku semasa kecil dalam keluarga dan lingkungan. Trauma mendalam yang terjadi secara berulang-ulang, menyebabkan penumpukan beban, sehingga pelaku mempunyai sifat benci, keras, dan mudah tersinggung. Akibatnya, mudah melakukan tindakan sadis (mutilasi). Dampak dari tindak pidana pembunuhan secara mutilasi ini sangat besar, disamping sadisnya pelaku dalam memperlakukan mayat korban, tetapi juga mengakibatkan kerugian bagi keluarga si terbunuh dari dua sisi, yaitu mereka kehilangan orang yang mencari nafkah dan hatinya sedih karena kehilangan orang yang dicintainya. Pembunuhan secara mutilasi ... 190 itu merupakan pembunuhan yang disengaja dan direncanakan ditambah dengan unsur kesadisan dari pelaku dalam menganiaya mayat korban (dalam hal ini memotong-motong mayat korban). Peran Psikolog Dalam Mengungkap Kasus Pembunuhan Disertai Mutilasi Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial, yang oleh Negara ditentang dengan sadar. Dari definisi yang formil sudah terlihat bahwa tentangan tersebut berupa hukum. 76 Oleh sebab itu kejahatan harus diberantas melalui penegakan hukum. Hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, yaitu usaha yang rasional dalam menanggulangi kejahatan, sebab disamping penanggulangan dengan menggunakan pidana, masih ada cara lain untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. 77 Salah satunya dengan pendekatan dan pendidikan psikologi bagi masyarakat. Penelitian tentang sifat psikopat yang ada sangat minim sekali, sangat sulit, dan mustahil, karena pengidap psikopat dapat memiliki sifat itu dengan tindakan hubungan yang manipulatif dan tidak mudah dideteksi. Hal tersebut disebabkan oleh karena sifat pengidap psikopat secara lahiriah atau fisik tidak tampak dari sikap yang hangat, cerdas, dan biasa tersebut. Indonesia sebagai negara yang mengalami krisis di semua bidang kehidupan, sangat kondusif memunculkan pemain-pemain tunggal pelaku psikopat, baik dengan kadar rendah maupun dengan kadar yang tinggi. Disinilah sangat diperlukan gerakan-gerakan dari psikolog untuk melakukan analisis psikologi dalam mengungkap kasus mutilasi. Psikologi sebagai suatu seni dapat menggunakan proffiling (jatidiri pelaku) dalam menyibak latar belakang pembunuhan pelaku dari sisi kejiwaan atau penyakit yang diderita. Lalu, polisi mencermati keterangan pelaku yang selalu berubah dengan kondisi psikologis seperti yang ada pada diri Ryan sekarang ini. Selain itu, mencermati apakah pelaku sadar atau tidak saat membunuh korban. Mengecek kondisi psikologis pelaku, apakah memiliki kepribadian ganda dan gangguan kepribadian disosiatif atau tidak. Mencermati modus operandi yang sama, yang dilakukan pelaku dalam menghabisi korban lainnya dan motif dari aksinya tersebut. Lalu juga lebih mencermati tanda tangan (signature) pelaku. Tugas psikologi forensik mengungkap suatu kasus dalam penyelidikan dan penyidikan, tidak bisa dipisahkan. Dalam menyelesaikan kasus kejahatan kriminolog tidak mengenal faktor penyebab tunggal (single factor caution), tetapi dijawab oleh aneka faktor (multiple factor caution). 76 Bonger, W.A, 1982, Pengantar Tentang Kriminologi, Cet VI, terjemahan R.A. Koesnoen. Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 23. 77 Sudarto, 1977, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hal. 101. ... 191 Faktor yang tidak kalah pentingnya adalah dari aspek psikologi pelakunya. Menurut teori psikoanalisis, tidak terpecahkannya konflik yang dihasilkan dalam trauma sejak masa kanak-kanak mengakibatkan ketidakteraturan kepribadian (mentaly disorder) dan tingkah laku agresif kepada seseorang. Apabila berbicara masalah perilaku yang agresif, kita tidak bisa lepas dari teori Freud, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai dua insting dasar: insting seksual dan insting agresif. Insting seksual atau libido adalah insting yang mendorong manusia untuk mempertahankan hidup, mempertahankan jenis, dan melanjutkan keturunannya. Adapun insting agresif adalah insting yang mendorong manusia untuk menghancurkan manusia lain. Kemampuan Analisis Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai aparat penegak hukum seperti diamanahkan dalam Undang-Undang (UU) 2/2002, sudah seharusnya dapat menegakkan hukum sebagaimana mestinya secara adil. Untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat yang sedang berurusan dengan hukum, seperti kasus mutilasi, Polri harus dapat melakukan tindakan, baik penyelidikan maupn penyidikan terhadap kasus tersebut. Dalam melakukan tugasnya itu, Polri khususnya penyidik dibekali dengan kemampuan dan keterampilan penyidikan tindak, pidana baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun di luar KUHP. Dalam tataran itu, dibutuhkan suatu kemampuan melihat, mengidentifikasi, menganalisis, dan menangani kasus mutilasi dengan memperhatikan kondisi psikis atau kejiwaan pelakunya. Akan lebih optimal lagi apabila penyidik Polri bekerja sama dan berkoordinasi dengan psikolog dalam mendalami latar belakang atau penyebab pelaku melakukan tindak kejahatannya. Adapun tugas psikologi forensik di dalam penyidikan, adalah mengetahui kondisi psikologis tersangka melalui proses asesmen mental tersangka. Yaitu, mendeteksi ada tidaknya keterbatasan intelektual terdakwa. Psikolog mendeteksi kondisi intelektualitas tersangka tindak pidana, dalam rangka memperlancar proses penyidikan kepolisian. Melakukan asesmen kondisi berisiko dan berbahaya dari tersangka, agar psikolog mendapatkan gambaran kemungkinan adanya kondisi berisiko dan berbahaya dari tersangka selama dalam proses penyidikan kepolisian. Melakukan asesmen kompetensi mental tersangka (competency/insanity), dengan tujuan untuk mendeteksi apakah tersangka memiliki kompetensi mental (sakit jiwa) atau tidak. Hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan mendeteksi kondisi sobriety. Mendeteksi kondisi sobriety dilakukan untuk mendukung kecurigaan polisi saat interogasi, apakah pelaku ... 192 dipengaruhi oleh obat-obatan atau tidak; dan apa pun hasil pemeriksaannya tidak dihentikan. Selain itu, membantu mendapatkan keterangan tentang motivasi tersangka yang sebenarnya. Dengan demikian, bantuan atau masukan dari psikolog menjadi pertimbangan bagi polisi. Untuk membantu proses penyelidikan dan penyidikan tersebut, penyidik Polri selain memperoleh bantuan dari psikolog dapat mudah menangani kasus mutilasi tersebut dengan dan atau dari (segi) ilmu psikologi forensik. Dalam taraf pencegahan maka psikolog dapat memberikan pendidikan mental bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pemikiran Laccasagne yang berpendapat bahwa “yang terpenting adalah keadaan sosial lingkungan kita, karena lingkungan merupakan suatu wadah pembenihan untuk kejahatan dan kuman adalah penjahatnya.” 78 Sehingga perbaikan mental melalui pendekatan psikologi dilakukan di dalam lingkungan sosial masyarakat. Masyarakat Indonesia kurang mendapatkan pendidikan mengenai kesehatan mental karena belum mengenal ilmu psikologi secara luas. Dalam hal ini masyarakat awam yang kurang mengenyam pendidikan. Masyarakat ndonesia kurang diajarkan bagaimana cara mengolah emosi, mengenali diri sendiri dengan baik, mengenali perubahan lingkungan. Fakta bahwa orang Indonesia belum mengenal psikologi secara luas itu tampak pada kenyataan bahwa di Indonesia, profesi psikolog jauh lebih sedikit daripada profesi dokter dan hanya sedikit rumah sakit di Indonesia yang menyediakan jasa psikolog. Padahal orang sakit biasanya mengalami kecemasan berlebihan, terutama bagi yang hampir meninggal dan menghadapi operasi. Penutup Kejahatan mutilasi biasanya terjadi tergantung kepada keadaan psikis si pelaku, dimana si pelaku cenderung mengalami gangguan kejiwaan. Tindak kejahatan ini biasanya pelaku melakukan tindakan mutilasi adalah dengan tujuan untuk membuat relasi antara dirinya dengan korban terputus dan agar jati diri korban tidak dikenali dengan alasan-alasan tertentu. Selain itu, mutilasi juga dapat menjadi bentuk penyaluran amarah atau sakit hati yang lama terpendam. Biasanya pelaku memiliki hubungan yang dekat dengan korban. Bisa juga karena ada pengaruh kehidupan keluarganya saat masih kecil. Kecemburuan juga dapat menjadi pendorong yang kuat, untuk melakukan tindakan mutilasi. Kejahatan mutilasi sering sekali terjadi dilakukan oleh orang-orang yang memang mengalami depresi dan 78 Abdul Wahid dan Muhamad Labib, 2005, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), Refika Aditama, Bandung, hal. 10-11. ... 193 gangguan kejiwaan, bahwa dengan tidak memotong-motong tubuh korbannya, pelaku sering sekali tidak puas untuk menyelesaikan kejahatannya. Untuk mengoptimalisasikan pengungkapan tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi maka diperlukan kerjasama penyidik dengan psikolog dalam mendalami latar belakang atau penyebab pelaku melakukan tindak kejahatannya. Adapun tugas psikologi forensik di dalam penyidikan, adalah mengetahui kondisi psikologis tersangka melalui proses asesmen mental tersangka. Hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan mendeteksi kondisi sobriety. Dalam taraf pencegahan maka psikolog dapat memberikan pendidikan mental bagi masyarakat. Pelaku kejahatan pembunuhan dan mutilasi merupakan orang yang berbahaya bagi lingkungan dan masyarakat. Oleh sebab itu untuk mencegah hal tersebut maka diperlukan dukungan dari lingkungan masyarakat. Pola kekerasan dalam pendidikan perlu dihilangkan, karena kekerasan hanya menimbulkan trauma bagi seseorang. Peran psikolog dalam penungkapan kasus perlu dioptimalkan dengan cara pelibatan psikolog pada menelusuri kondisi kejiwaan dari pelaku. Psikolog diharapkan dapat memberikan pendapat ahlinya kepada penyidik sehubungan dengan pemeriksaan perkara. DAFTAR PUSTAKA BUKU Abdul Wahid dan Muhamad Labib, 2005, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), Refika Aditama, Bandung. Bonger, W.A, 1982, Pengantar Tentang Kriminologi, Cet VI, terjemahan R.A. Koesnoen. Ghalia Indonesia, Jakarta. Sudarto, 1977, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni Bandung. INTERNET Anonim, “Baekuni (Babe) Pembunuh Keji Anak Jalanan”, http://ekstrimwebz.blogspot.com/2010/01/baekuni-babe-pembunuh-keji-anak-jalanan.html, diakses pada 3 Agustus 2011. Eko Hartanto, 31 Juli 2008 , “Psikologi Forensik Kasus Mutilasi”, http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2008/07/31/24377/Psikologi.Forens ik.Kasus.Mutilasi, diakses pada 3 Agustus 2011. ... 194 AKIBAT HUKUM BERAKHIRNYA PERJANJIAN FRANCHISE TERHADAP KEWAJIBAN FRANCHISEE DALAM MENJAGA RAHASIA DAGANG Made Emy Andayani Citra Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar [email protected] Abstract: Franchise business is a growing business in the field of trade in goods and services. In business franchise, the franchisor as the franchise giver sell as a working system to the franchisees as the franchisee receivers within a specified period. Trade secrets are being sold by the franchisor to the franchisee. To protect trade secrets, then the clauses of the trade secrets contained in the franchise agreement. If this agreement ends, the franchisee may no longer use such trade secrets or use confidential commercial without right. Franchisees also must ensure that employees do not violate trade secrets, when he was still working or has stopped working at the company's franchisee. Key words: Franchise agreement, trade secret and frenchisee’s obligation. Pendahuluan Sistem franchise adalah salah satu mekanisme pemasaran bisnis yang semakin berkembang di dunia. Berkat globalisasi ekonomi, perkembangan ini juga sampai ke Indonesia. Franchise adalah sistem pemasaran barang dan atau jasa dan atau teknologi, yang didasarkan pada kerjasama tertutup (antara franchisor dan franchisee) dan terusmenerus antara pelaku-pelaku independen (franchisor) dan terpisah baik secara hukum dan keuangan, dimana franchisor memberikan hak pada franchisee, dan membebankan kewajiban untuk melaksanakan bisnisnya sesuai dengan konsep dari franchisor. 79 Ada banyak perusahaan franchise milik asing dan milik pengusaha tanah air yang beroperasi di Indonesia seperti Pizza Hut, KFC, Es Teler 77, Primagama dan sebagainya. Di Indonesia, istilah franchise diterjemahkan dengan “waralaba.” Istilah waralaba secara normative diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, “Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.” 79 Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2007, Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern, Refika Aditama, Bandung, hal. 134. ... 195 Waralaba juga melibatkan pemberian confidential information dan know how; dari pihak pemberi waralaba/ franchisor kepada penerima waralaba/franchisee. Sebagai pengganti istilah confidential information kadang-kadang juga digunakan istilah rahasia dagang (trade secrets), Unsur rahasia dagang memegang peranan yang sangat penting terutama dalam waralaba yang termasuk chain-style business, contohnya resep pembuatan Kentucky Fried Chicken atau Pizza Hut. Namun, tidak tertutup kemungkinan pihak franchisor masih tetap menahan sebagian dari rahasia dagang dengan tujuan agar franchisee tetap bergantung kepada franchisor, misalnya dalam bentuk ramuan siap pakai. Dalam kasus tersebut, pihak franchisee harus tetap menggunakan ramuan dalam bentuk siap pakai dari franchisor, tanpa mengetahui cara meraciknya. Semuanya bergantung pada isi perjanjian waralaba. 80 Rahasia dagang dalam usaha franchise harus dijaga sebagaimana yang diatur dalam perjanjian waralaba. Namun yang menjadi permasalahan hukum apakah ketika perjanjian waralaba berakhir, rahasia dagang ini masih tetap dijaga, bagaimana pula akibat hukum jika pihak yang pernah menerima waralaba dan atau karyawannya menggunakan rahasia dagang dengan mereknya sendiri setelah perjanjian waralaba berakhir. Hal inilah yang sangat menarik untuk dikaji dalam penelitian ini. Aspek Hukum Bisnis Franchise Bentuk usaha franchise adalah suatu usaha dengan format yang sederhana dan bertujuan untuk memperluas pangsa pasar. Bisnis franchise itu sendiri dimulai pada tahun 1800-an di Inggris ketika system tied house digunakan oleh pembuat bir untuk memasarkan produk mereka. Ide tersebut kemudian diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1851 oleh perusahaan mesin jahit Singer untuk memperluas jaringan pemasaran mereka dan perbaikan mesin jahit mereka kepada konsumennya. Ide franchising ini dimatangkan kembali oleh General motor pada tahun 1898 dengan menggunakan sistem “Independent business” untuk meningkatkan penjualan dan jaringan distribusi tanpa mengeluarkan banyak uang. Cara ini kemudian diikuti beberapa perusahaan ternama lainnya seperti perusahaan obat “Rexall” dan perusahaan minuman seperti Coca Cola dan Pepsi.Perkembangan semakin pesat sampai kata waralaba diambil dari kata franchise yang di Indonesiakan kata waralaba tersebut bisa diartikan dengan kata Wara yang artinya Banyak sedangkan laba yang berarti untung. 81 80 Adrian Sutedi, 2008, Hukum Waralaba, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 106 Taufik Hidayat, “Waralaba – Sejarah dan Perkembangan Waralaba Indonesia”, 10 Juni 2011, http://www.konsultanwaralaba.com/waralaba-sejarah-dan-perkembangan-waralaba-indonesia/, akses pada 2 Juli 2012. 81 ... 196 Di dalam waralaba dikenal suatu istilah yang disebut sebagai mem-franchise-kan, mem-franchise-kan adalah suatu metode perluasan pemasaran dan bisnis. Suatu bisnis memperluas pasar dan distribusi produk serta pelayanannya dengan membagi bersama standart pemasaran dan operasional sehingga pemegang franchise yang membeli suatu bisnis menarik manfaat dari kesadaran pelanggan akan nama dagang, sistem teruji dan pelayanan lain yang disediakan pemilik franchise. 82 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Rahyn 2007 tentang Waralaba dikenal dua pelaku dalam usaha waralaba yakni pemberi waralaba dan penerima waralaba. Pemberi waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba. Pemberi waralaba juga diistilahkan dengan franchisor. Penerima waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba. Penerima waralaba disebut juga dengan franchisee. Franshise merupakan kerjasama bisnis dan secara teknis dapat dipahami sebagai suatu metode perluasan pasar yang digunakan oleh sebuah perusahaan yang dianggap sukses dan berkehendak meluaskan distribusi barang atau jasa melalui unit-unit bisni eceram yang dijalankan oleh pengusaha-pengusaha independen dengan menggunakan merek dagang atau merek jasa, teknik pemasaran dan berada di bawah pengawasan dari perusahaan yang hendak meluaskan pasarnya dengan imbalan-imbalan pembayaran fees dan royalties. 83 Martin D. Jern melihat ada empat unsur yang terkandung dalam franchise yaitu: 1. 2. 3. 4. Pemberian hak untuk berusaha dalam bisnis tertentu. Lisensi untuk menggunakan tanda pengenal usaha, biasanya suatu merek dagang atau merek jasa, yang akan menjadi ciri pengenal dari bisnis franchisee. Lisensi untuk mengggunakan rencana pemasaran dan bantuan yang luas oleh franchisor kepada franchisee. Pembayaran oleh franchisee kepada franchisor berupa sesuatu yang bernilai bagi franchisor selain dari harga borongan bonafide atas barang yang terjual. 84 Franchisor dalam jangka waktu tertentu memberikan lisensi kepada franchisee untuk menggunakan tanda pengenal usaha franchisor melakukan usaha pendistribusian barang atau jasa. Distribusi tersebut dilakukan di bawah nama identitas franchisor dalam wilayah tertentu dan usaha tersebut harus dijalankan sesuai dengan prosedur dan cara yang 82 Douglas J Queen, 1993, Pedoman Membeli dan Menjalankan Franchise, Elex Media Komputindo, Jakarta, hal. 4-5. 83 Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, op.cit., hal. 134-135. 84 Juajir Sumardi, 1995, Aspek-aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 18. ... 197 ditentukan dalam perjanjian waralaba. Pemberi waralaba atau franchisor wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian dan pengembangan kepada penerima waralaba/ franchisee secara berkesinambungan. Atas kewajiban yang dilakukan franchisoe tersebut maka penerima waralaba wajib membayar sejumlah uang berupa initial fee dan royalty . Franchisor pada dasarnya adalah pihak yang memiliki sistem atau cara-cara dalam berbisnis. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba disebutkan bahwa pemberi waralaba harus memberikan prospektus penawaran waralaba kepada calon penerima waralaba pada saat melakukan penawaran. Prospektus penawaran waralaba memuat paling sedikit mengenai: a. data identitas pemberi waralaba; b. legalitas usaha pemberi waralaba, c. sejarah kegiatan usahanya; d. struktur organisasi pemberi waralaba; e. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir; f. jumlah tempat usaha; g. daftar penerima waralaba; dan a. hak dan kewajiban pemberi waralaba dan penerima waralaba. Franchisee adalah pihak yang membeli waralaba atau sistem dari pemberi waralaba (franchisor) sehingga memiliki hak untuk mejalankan bisnis dengan cara-cara yang dikembangkan oleh pemberi waralaba. Untuk melindungi kepentingan pengusaha kecil di Indonesia, maka dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba ditentukan bahwa: (1) Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan/atau jasa yang ditetapkan secara tertulis oleh Pemberi Waralaba. (2) Pemberi Waralaba harus bekerjasama dengan pengusaha kecil dan menengah di daerah setempat sebagai Penerima Waralaba atau pemasok barang dan/atau jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemberi Waralaba. Hubungan hukum antara franchisor dan franchisee dituangkan dalam suatu perjanjian waralaba. Di dalam Perjanjian waralaba harus mempunyai syarat-syarat, adapun syaratsyarat yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Kesepakatan kerjasama sebaiknya tertuang dalam suatu perjanjian waralaba yang disahkan secara hukum . 2. Kesepakatan kerjasama ini menjelaskan secara rinci segala hak, kewajiban dan tugas dari Franchisor dan Franchisee. 3. Masing-masing pihak yang bersepakat sangat dianjurkan, bahkan untuk beberapa negara dijadikan syarat, untuk mendapatkan nasihat dari ahli hukum yang ... 198 kompeten, mengenai isi dari perjanjian tersebut dan dengan waktu yang dianggap cukup untuk memahaminya 85 Penuangan hubungan hukum antara franchisor dengan franchisee dalam suatu perjanjian berfungsi untuk menjamin kepastian hukum diantara para pihak. H. Salim H.S, H. Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih menyebutkan bahwa fungsi kontrak terbagi atas 2 (dua) jenis yaitu sebagai berikut : a. Fungsi yuridis kontrak adalah dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. b. Fungsi ekonomi kontrak adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih rendah. 86 Dalam kepentingan bisnis, perjanjian sangat penting. Hubungan antara perjanjian dengan kegiatan bisnis ini digambarkan oleh Sucthitthra Vasu, sebagai berikut: In the commercial world, contracts frequently facilitate business dealings. It is therefore imperative for the layperson to have a basic understanding of the subject matter. Essentially, a contract is an agreement, ussualy made between two parties whereby a commodity is sold or service provided for payment known as the price. Contracts can be categorized under two broad headings such as the contract for sale of goods or a contract for service. 87 Dalam hubungan bisnis, perjanjian menjadi fasilitas dalam kesepakatan bisnis. Perjanjian menggariskan pengertian-pengertian dasar mengenai suatu objek perjanjian. Perjanjian juga mengjadi substansi penting dalam menjalankan bisnis waralaba. Ketentuan mengenai perjanjian waralaba tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Dalam Pasal 4 disebutkan: (1) Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia. (2) Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam bahasa asing, perjanjian tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Lebih lanjut dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba disebutkan bahwa: Perjanjian Waralaba memuat klausula paling sedikit: a. nama dan alamat para pihak; b. jenis Hak Kekayaan Intelektual; c. kegiatan usaha; d. hak dan kewajiban para pihak; 85 Gunawan Widjaja, 2003, Lisensi atau Waralaba, Suatu Panduan Praktis, Cetakan Kedua, Radja Grafindo Persada, Jakarta, hal 80. 86 HAL. Salim HAL. S, HAL. Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih, 2008, Perancangan Kontrak & Memporandum of Understanding (MoU), Sinar Grafika, Jakarta, hal. 23. 87 Sucthitthra Vasu, 2006, Contract Law For Business People A Practical Guide to Negotiating and Drafting Better Contracts, Rank Book, Singapore, hal. 14. ... 199 e. bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba; f. wilayah usaha; g. jangka waktu perjanjian; h. tata cara pembayaran imbalan; i. kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris; j. penyelesaian sengketa; dan k. tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba menentukan ayat (1) Perjanjian Waralaba dapat memuat klausula pemberian hak bagi Penerima Waralaba untuk menunjuk Penerima Waralaba lain. (2) Penerima Waralaba yang diberi hak untuk menunjuk Penerima Waralaba lain, harus memiliki dan melaksanakan sendiri paling sedikit 1 (satu) tempat usaha Waralaba. Perjanjian waralaba wajib ditaati oleh pemberi maupun penerima waralaba. Klausula Rahasia Dagang dan Akibat Hukumnya Bisnis franchise pada dasarnya adalah bisnis yang menjual system kerja. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba menentukan Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. memiliki ciri khas usaha; b. terbukti sudah memberikan keuntungan; c. memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis; d. mudah diajarkan dan diaplikasikan; e. adanya dukungan yang berkesinambungan; dan f. Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar. Hak kekayaan intelektual adalah bagian yang harus ada dalam perjanjian franchise. Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar adalah Hak Kekayaan Intelektual yang terkait dengan usaha seperti merek dan/atau hak cipta dan/atau paten dan/atau lisensi dan/atau rahasia dagang sudah didaftarkan dan mempunyai sertifikat atau sedang dalam proses pendaftaran di instansi yang berwenang. Perjanjian franshise selalu memuat klausula yang melarang para pihak (franchisor maupun frachisee) untuk memberitahukan rahasia dagang kepada pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan bisnis. Klausula kerahasian ini amat penting dalam suatu perjanjian franshise karena bila rahasia dagang diketahui oleh pihak lain maka akan menimbulkan competitor/ pesaing baru dalam bidang bisnis barang/ jasa yang sama. Idealnya masalah yang diatur di dalam klausul kerahasian adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian ... 200 franshise diwajibkan menjaga dengan baik setiap informasi yang bersifat rahasia dengan penjatuhan sanksi yang berat apabila salah satu pihak melanggarnya. 88 Rahasia dagang adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam bisnis waralaba. Franchisor adalah pihak yang memiliki rahasia dagang dan “meminjamkannya” kepada franchisee. Berdasarkan Pasal angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang disebutkan bahwa “Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.” Pasal 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menentukan bahwa “Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.” Suatu informasi dapat digolongkan sebagai rahasia dagang apabila memenuhi kriteria sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yakni: 1. Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. 2. Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. 3. Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. 4. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya atau memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Pemilik rahasia dagang yang dalam hal ini adalah franchisor atau pemberi waralaba dapat menentukan klausul perjanjian rahasia dagang. Untuk menjaga rahasia dagang tersebut maka pihak franchisee atau penerima waralaba harus tunduk pada ketentuan rahasia dagang yang dimuat dalam perjanjian waralaba tersebut. Untuk menjamin rahasia dagang maka dalam perjanjian waralaba juga dapat dimuat kewajiban dari pihak franchisee untuk tetap menjaga kerahasiaan dan tidak menggunakan rahasia dagang tersebut meskipun perjanjian waralaba antara franchisor dengan franchisee 88 Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, op.cit., hal. 140. ... 201 berakhir. Pihak franchisee dalam menjaga rahasia dagang juga harus mencantumkan kewajiban untuk menjaga rahasia dagang dan larangan untuk menggunakan rahasia dagang tersebut selain untuk yang diperbolehkan kepada karyawan yang dipekerjakan oleh franchisee. Klausula tersebut dapat dituangkan di dalam perjanjian kerja atau dituangkan tersendiri dalam perjanjian antara pemberi kerja dengan tenaga kerja. Coca-cola dengan formula minumannya yang terkenal yang dikemas dalam kaleng berwarna merah dan botol berdesain unik, telah memiliki resep rahasia yang berumur lebih dari 125 tahun. Dalam situsnya www.thecoca-colacompany.com, dikabarkan bahwa resep formula asli saat ini disimpan di sebuah rumah di The World of Coca-Cola di Atlanta di mana sebelumnya disimpan di SunTrust Bank di Atlanta sejak 1925. Coca-cola membatasi akses kepada formula tersebut dengan hanya mengizinkan beberapa orang eksekutifnya. 89 Pembatasan ini sah menurut hukum dan tidak melanggar asas keseimbangan dalam perjanjian. Pelanggaran terhadap rahasia dagang dalam perjanjian waralaba memiliki akibat hukum baik secara perdata maupun secara pidana. Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menyebutkan: (1) Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berupa: a. gugatan ganti rugi; dan/atau b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri. Penyelesaian gugatan juga dapat dilakukan oleh para pihak melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, pelanggaran rahasia dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Selanjutnya dalam Pasal 14 ditentukan bahwa “Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Perbuatan mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang 89 Lucky Setiawati, “Pertanyaan: Rahasia Dagang dan Perlindungan Formula Resep Makanan”, Rabu, 27 June 2012, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4feadb7627be1/rahasia-dagang-dan-perlindunganformula-resep-makanan, ... 202 sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang tidak dianggap pelanggaran Rahasia Dagang apabila: a. b. tindakan pengungkapan Rahasia Dagang atau penggunaan Rahasia Dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat; tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan. Pelanggaran rahasia dagang dapat juga diselesaikan secara pidana. Dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang ditentukan bahwa: (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan delik aduan. Meskipun perlindungan tentang rahasia dagang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang namun klausula-klausula tentang rahasia dagang ini tetap harus dicantumkan dalam perjanjian waralaba. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menjadi dasar hukum dalam ketentuan rahasia dagang pada perjanjian waralaba. Kewajiban hukum untuk tidak melanggar rahasia dagang ini bukan hanya diwajibkan bagi franchisee saja namun juga bagi karyawan yang dipekerjakan oleh franchisee. Dalam hal ini franchisee mempunyai kewajiban dalam menjamin rahasia dagang melalui hubungan kerja antara franchisee sebagai pengusaha dan karyawan sebagai tenaga kerja. Penutup Akibat hukum berakhirnya perjanjian franchise tetap membebankan kewajiban bagi franchisee untuk menjaga rahasia dagang yang pernah diketahuinya. Franchisee juga dibebankan kewajiban untuk mencegah pelanggaran rahasia dagang yang dilakukan oleh karyawan dan mantan karyawannya. Oleh sebab itu klausula tentang rahasia dagang wajib dicantumkan dalam perjanjian waralaba dan perjanjian kerja antara franchisee selaku pengusaha dan karyawannya dalam perjanjian kerja. Pelanggaran terhadap rahasia dagang dapat diproses secara perdata dan secara pidana. ... 203 DAFTAR PUSTAKA BUKU Adrian Sutedi, 2008, Hukum Waralaba, Ghalia Indonesia, Bogor. Gunawan Widjaja, 2003, Lisensi atau Waralaba, Suatu Panduan Praktis, Cetakan Kedua, Radja Grafindo Persada, Jakarta. Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2007, Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern, Refika Aditama, Bandung. Juajir Sumardi, 1995, Aspek-aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional, Citra Aditya Bakti, Bandung. Queen, Douglas J., 1993, Pedoman Membeli dan Menjalankan Franchise, Elex Media Komputindo, Jakarta. Salim H.S, H. Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih, 2008, Perancangan Kontrak & Memporandum of Understanding (MoU), Sinar Grafika, Jakarta. Vasu, Sucthitthra, 2006, Contract Law For Business People A Practical Guide to Negotiating and Drafting Better Contracts, Rank Book, Singapore. INTERNET Lucky Setiawati, “Pertanyaan: Rahasia Dagang dan Perlindungan Formula Resep Makanan”, Rabu, 27 June 2012, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4feadb7627be1/rahasia-dagang-danperlindungan-formula-resep-makanan, diakses pada 2 Juli 2012. Taufik Hidayat, “Waralaba – Sejarah dan Perkembangan Waralaba Indonesia”, 10 Juni 2011, http://www.konsultanwaralaba.com/waralaba-sejarah-dan-perkembanganwaralaba-indonesia/, akses pada 2 Juli 2012. SUMBER HUKUM Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. ... 204 THE ROLE OF THE CUSTOMARY VILLAGE IN CULTURAL TOURISM WITH ENVIRONMENTAL VISION (CASE STUDY ON THE DEVELOPMENT OF TOURISM VILLAGE IN BALI) I Wayan Wiasta, I Wayan Gde Wiryawan, I Nyoman Edi Irawan, and Dewi Bunga Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar [email protected] and [email protected] Abstrak: Desa wisata adalah salah satu objek wisata yang kini dikembangkan di Bali. Desa wisata menyajikan pemandangan sawah, sungai dan aktivitas warga desa. Keberadaan desa wisata dengan sendirinya mendorong keterlibatan warga desa untuk melestarikan lingkungan dan sekaligus mampu meningkatkan pendapatan warga desa. Desa adat memiliki peranan dalam menggagas pembentukan desa budaya dan menjaga kelestarian desa wisata. Peranan ini diwujudkan dengan pembangunan fisik seperti pembangunan rumah dengan arsitektur Bali, taman dengan tanaman khas Bali dan pembangunan non fisik yakni persiapan mental warga desa adat untuk menjadi tuan rumah dari suatu objek wisata dan peningkatan taraf pendidikan. Peranan desa adat dalam pengembangan desa wisata sangat dipengaruhi oleh tanggung jawab desa adat atas kelestarian lingkungan sebagaimana yang diatur dalam hukum nasional dan hukum adat mereka. Peranan desa adat ini juga dipengaruhi oleh keterbukaan pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat lokal. Kata Kunci : desa adat, pariwisata budaya, lingkungan dan desa wisata. Introduction The development of the tourism sector as part of national development seems to be a rapidly growing sector. This can be seen from the increasing amount of foreign exchange generated from this sector. Country foreign exchange earnings from tourism in 2011 exceeded 8.5 billion dollars or about Rp 75 trillion. This figure ranks the tourism sector as fifth contributor to foreign exchange. The value of 8.5 billion U.S. dollars was 11.8 percent greater than the acquisition of 2010 which amounted to 7.6 billion U.S. dollars. Increase in national income is derived from the increase in the number of foreign tourists coming to Indonesia. In 2011 foreign tourists who travel to Indonesia was as many as 7.6 million people, up 8.5 percent compared to year 2010. 90 The progress of tourism the sector can be seen from the rise of tourism businesses around the world such as the hospitality business, travel agent business, food & beverage business, tourist attraction business and others. The development of the tourism sector gives a fairly high economic benefit. These economic benefits take effect on state revenues in 90 Pos Kota, “Tembus Rp.75 Triliun, Devisa Negara dari Pariwisata Tahun 2011”, http://poskota.co.id/berita-terkini/2011/12/30/tembus-rp-75-triliun-devisa-negara-dari-pariwisata-tahun-2011, accessed on May 9, 2012. ... 205 general and in particular the welfare of the surrounding community. The tourism sector indirectly (working in hotels, tourist attractions, transportation and souvenirs) employs 8 percent and directly (working in hotels and resorts) 3 percent. 91 Tourism development include eco-tourism such as coastales, mountains, caves, etc. and cultural tourism such as traditional ceremony, traditional clothing, dance,etc. Both have a special attraction for tourists. The development of eco-tourism and cultural tourism need to synergize. Therefore, the tourism sector should be regulated in the act. In Indonesia, the provision of tourism is arranged in the Act of Republic of Indonesia No. 10 of 2009 concerning Tourism. This act is expected to achieve a sustainable tourism destination in the direction of national development. The Province of Bali is categorized as “the best destination in the world.” Bali is known as the best destination because it has a variety of cultures. Therefore, the provincial government determined that the development of tourism in Bali is a cultural tourism. This policy was formulated in the Bali Provincial Regulation No. 3 of 1991 concerning Cultural Tourism. Cultural tourism can not be separated from the role of communities as set out in Article 12, which expressly states that: (1) The local government gives the widest opportunity for the public to play a role in organizing tourism. (2) In the framework of decision-making process, the local government should involve the community in planning, implementation and supervision. (3) full implementation of the community as prescribed in paragraph (2) shall be established by decree of the Governor. The role of the community in the implementation of tourism includes a variety of sectors that support tourism, as well as the environmental sector as the main support of cultural tourism. Environment and tourism are the two things that can not be separated because of the attraction to tourisrs that will be created from the existence of good environmental management. Environment in cultural tourism consists of the physical environment and social environment. One form of cultural tourism is the environmentally sustainable traditional villages. Traditional villages as a tourist attraction which will now be reffered to as “tourism village”. Tourism village is one tourism sector that is now being developed in Bali. One of the villages that has been defined as a tourism village in Bali is Bongkasa Pertiwi village. This 91 Republika, “Devisa Pariwisata Ditarget 9 Miliar Dolar AS”, http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/01/24/lyb7as-devisa-pariwisata-ditarget-9-miliar-dolaras, accessed on May 9, 2012. ... 206 village is located in North Badung, Bali. This Tourism village overlooks rice fields, rivers and the activities of the villagers. This attraction could attract domestic and foreign tourists. Tourism village development is the result of thinking through the Government of Badung regency government in creating an ecology-based tourism so-called ecological tourism. This concept is expected to have tourism appeal because of the social life of the Balinese people who still have not been influenced by foreign cultures. The development of a tourism village doesn’t only aim to change the face of the village, but rather resemble the natural conditions in the village area, this has become a unique tourist attraction. Tourism village is one attempt to produce a new tourism product. This attraction is not intended to change the village spatial planning, tourism village will not lead to the addition of five-star accommodation facilities, but rather offer an alternative to existing facilities. The need for the presence of tourist accommodation facilities in the village will be directed to people’s houses. In achieving these objectives they will face many obstacles, among others. It can be a matter of management, behavioral and cultural barriers to community tourism on the environment. 92 The existence of a tourist village in itself encourage the involvement of villagers to maintain and preserve the rural beauty of the environment. The Role of Customary Village in the Tourism Village Development Construction of tourism village is directed at the development of tourism in the region involving the role of society to the fullest. In conjunction with the construction, according to the UN definition of the role is as an active and meaningful involvement of the mass of the population at different levels (a) in the process of formation of the decision to determine the social objectives and the allocation of the sources to achieve those goals, (b ) implementation of programs and volunteer projects, and (c) use the results of a program or project. 93 Therefore, the involvement of the villagers is to play a role in the processes of planning, implementation and operations. Potential development at Bongkasa Pertiwi Village has been carried out since 1990 and is directly aimed at the determination of this village as the tourism village. 94 In the juridical determination of the village as a tourist village, Bongkasa Pertiwi is based on the 92 2012. 93 Era Baru News, “Sawah di Kabupaten Badung Bali”, www.erabarunews.com, accessed on May 9, Slamet, Y, 1993, Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi, Sebelas Maret University Press, Surakarta, p. 24 94 Interview with I Made Suarjana, The Leader of Bongkasa Pertiwi Village. ... 207 Decree No. 47 of 2010 on the Determination Area to the Village in Badung regency on 15 September 2010 and formally accepted by the Village Bongkasa pertiwi on January 5, 2011. 95 Bongkasa Pertiwi tourism village presents the beauty of nature, such as the use of the Ayung River for rafting tours and traditional activities like farming. In the development of this tourism village, the attraction is not just the physical region but also the social life of rural villagers. Development of this tourism village makes the role of society as something absolute. 96 The role of the public is encouraged because of the basic psychological needs of each individual. This means that people want to be in a group to engage in any activity. 97 Bongkasa Pertiwi village Government has realized that community involvement in the development of the potential of the Bongkasa Pertiwi village will also be determined by the pivotal role played by both the provincial government, district and village government. Each group must work together to create sustainable development. Development activities are mostly government business. As a comparison, in countries that embrace pure socialism, all development activities are the responsibility of the government. But in a state of the big role of the country, the role of society is also needed to ensure the success of development. 98 In fact, the contribution of the community in addition to the private sector (non governmental organizations and the government itself) are viewed as an essential contribution in development. Projects that have reflected the needs of the community, compared with the projects that have not involved the community have produced favourable results. This means, that society is not only seen as an object, but the goal is to involve the community as a subject, in this case they act as development partners in a process that begins with planning, programming to the implementation of even the operation and maintenance. Thereby increasing the sense of the responsibility of society to preserve the environment because in principle the Bongkasa Pertiwi village has actually felt a significant change in the pattern of community life, for example agriculture as a livelihood and also be a form of tourism too. Development of this village is a shared responsibility between the village goverment and the community. The Central, Provincial and District Governments serve as advocates and coaches. As a consequence, the role of society should be an essential part of a development program. See the phenomenon at the Bongkasa Pertiwi village government as 95 Ibid. Ibid. 97 Salusu, J., 1996, Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Non Profit, Gramedia, Jakarta, 96 p. 36 98 Ginandjar Kartasasmita, 1997, Administrasi Pembangunan, LP3ES, Jakarta, p. 49. ... 208 being indispensable to realize the Village of Spatial Regulation 99 also sets out the role of village communities which are, in the case of Bongkasa Pertiwi, a very positive response by the community. 100 The role of the community opens the possibility of decisions being taken based on the needs, priorities and capabilities of the villagers. Villagers in Bongkasa Pertiwi are involved in the planning process and to the maintenance of environmental management,this means that the development in the rural environment is very effective is the running of Bongkasa Pertiwi village. 101 Tourism village development centered on human interests, and not just a tool of development itself. Thus the result will be in accordance with the aspirations, social and cultural conditions and the economic capacity of the community in question. This led to the village community of Bongkasa Pertiwi village not feel any constraints in environmental management in the development of Cultural Tourism-based environment. 102 In general, the role of Bongkasa Pertiwi customary village in developing the tourism village conducted in two forms namely the form of material donations and the immaterial contribution of thought and time in making decissions and activities undertaken to support the existence of a tourism village. The role in the community development can be from planning to the operation of tourism village development. The role of communities in the planning process is high because most people are invited in the planning process and are involved in making decisions. Thus the bongkasa pertiwi village was formed and customised by the villagers itself. Involvement of a customary tourist in ensuring the sustainability of the tourism village are made real by a variety of activities in environmental management in the village. This role is realized by the physical development such as building a house with Balinese architecture or planting a Balinese garden with plants. Physical development-oriented environmental management are embodied in mutual aid activities, brown tree planting and reforestation. 103 Non-physical development carried out by indigenous villagers in mental preparation to be the host of an attraction and increasing the level of education of the villagers. 99 Ibid Interview with Mr. Milih, the villager of Bongkasa Pertiwi Village. 101 Ibid 102 Ibid 103 Interview with Ardjana, the willager of Bongkasa Pertiwi Village. 100 ... 209 The Factors That Influence The Role of Customary Village in The Tourism Village Development Village tourism development together with the environmental needs and the community role which in this case is a customary village. The role of the customary village is influenced by these factors. Based on the theory of the operation of law by Chambliss and Seidman, can be explained that the working of the law in a society influenced by many factors: social, economic, political, cultural, environmental and so on. 104 Broadly speaking, the operation of law in society will be determined by several key factors. These factors can be: a. b. c. d. Normative juridical (concerning the rule making legislation) Enforcement (of the parties and the role of government): Juridical and sociological factors (related to economic considerations and the legal culture of business); Consistency and harmonization between the politics of law in constitutional law with the underlying law product. 105 The role of the customary village in tourism village development is strongly influenced by the responsibility of the villagers for environmental sustainability as set out in international law, national law and their traditional law. Environmental concern was first expressed in the Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, known as the Stockholm Declaration of 1972. In Article 2 of the Declaration stated: The natural resources of the earth, including the air, water, land, flora and fauna and especially representative samples of natural ecosystems, must be safeguarded for the benefit of present and future generations through careful planning or management, as appropriate. Environmental protection through national law can be seen in Article 28 h of Law Number 32 Year 2004 on Regional Government. In the implementation of autonomy, local region have an obligation to preserve the local environment. This provision became the basis for the village government to be involved in the development of environmentally friendly tourism. This legal obligation is arranged in the customary law in the village. Elaboration of the culture and environment in the tourism culture is normatively regulated in the Act No. 10 of 2009 concerning Tourism. Article 5 a state of Tourism is held in high regard to the principle of religious norms and cultural values as a manifestation of the concept of life in the balance of the relationship between man and God Almighty, the 104 Pujirahayu, Esmi Warassih, 2005, Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang, Suryandaru Utama, p. 13-14. 105 Suteki, 2007, Hak Atas Air di Tengah Liberalisasi Hukum dan Ekonomi Dalam Kesejahteraan, Pustaka Magister Kenotariatan, Semarang, p. 59-60 ... 210 relationship between man and man, and the relationship between humans and the environment. Article 5 d declare “tourism organized with the principle of maintaining the natural and environmental sustainability.” Bongkasa pertiwi as a customary village community organization, recognized and nurtured by the government to maintain and preserve the moral values based on cooperativeness and family, and to help improve the convenience of the government. The role must contain the elements of the active involvement of stakeholders in an organization that has the working apparatus of government and society. The role of the customary village requires openness of local government in developing local community-based tourism. The other factors from the government role to the community are through the provision of counseling, information dissemination and provision of planting, while also giving stimulants in the form of material and funds. Tourism village development in Bongkasa Pertiwi is one of the Badung regency government efforts to evenly spread Badung tourism development between the North area and South area of Badung. In the development of tourism village is possible involvement of a third party as a companion. Definition of a third party as a companion here is a group that is involved in various development activities, whether carried out by NGOs, Social Foundations and Universities. They can play a role through community development efforts, helping synthesizing approaches to development from above and below, to help organize and carry out joint activities and a variety of activities as a mediator or catalyst development. Development of a tourism village will take place optimally if private parties want to engage actively in the activities of corporate social reponsibility. The private sector is the Rafting companies. The companies are utilizing the Ayung river to support the recreational facilities in this tourist village. Operationally, rafting companies have contributed funds in the organization of activities in the village. Rafting companies also provide an opportunity for villagers to work at the company. Together with customary villages and communities, the rafting companies have to preserve the natural environmental in the Bongkasa Pertiwi. The working of the law in a society strongly influenced by social forces that exist in society. Robert B. Seidman stated that any action will be taken by stakeholders, executive agencies and law makers are always in the scope of the complexity of social forces, cultural, economic and political, and so forth. The whole social forces that always come to work in any attempt to enable the rules and regulations, implementing the sanctions, and in all ... 211 activities of the executing agencies. 106 Implementing norms will often consist of instructions to and about the institutions and processes of the law. 107 The legal protection of tourism village can be optimal if there is a strong rule and consistent application of sanctions for offenders. Conclusion Customary villages have a role in creating and preserving the tourism village. This role is realized by the physical development such as building a house with Balinese architecture, a garden with Balinese plants and non-physical development such as mental preparation for a host of tourism object and increasing the level of education. The role of a customary village in tourism village development is strongly influenced by the customary village responsibility for environmental sustainability as set out in national law and customs. The role of a customary village is also influenced by the transparency of local government in developing tourism based on local community. In the development of tourism village needed the necessary cooperation between the customary villages, local government, corporate, academic and community institutions or social organizations. This cooperation is conducted with the formulation, implementation and evaluation of policies. REFERENCES BOOKS Allot, Antony, 1980,The Limits of Law, Butterworths, London. Ginandjar Kartasasmita, 1997, Administrasi Pembangunan, LP3ES, Jakarta. Pujirahayu, Esmi Warassih, 2005, Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis, Suryandaru, Semarang. Salusu, J., 1996, Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Non Profit, Gramedia, Jakarta. Slamet, Y, 1993, Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi, Sebelas Maret University Press, Surakarta. Suteki, 2007, Hak Atas Air di Tengah Liberalisasi Hukum dan Ekonomi Dalam Kesejahteraan, Pustaka Magister Kenotariatan, Semarang. 106 Siti Mariyam, Pergeseran Kebijakan Dalam Pelayanan Publik Pada badan usaha milik negara (BUMN) (Dalam Perspektif Hukum dan Kebijaksanaan Publik), Thesis, Post Gradiation Program of Dipponegoro University, Semarang, 2007, p. 208-209. 107 Antony Allot, 1980,The Limits of Law, Butterworths, London, p. 23. ... 212 ARTICLES Era Baru News, “Sawah di Kabupaten Badung Bali”, www.erabarunews.com, accessed on May 9, 2012. Pos Kota, “Tembus Rp.75 Triliun, Devisa Negara dari Pariwisata Tahun 2011”, http://poskota.co.id/berita-terkini/2011/12/30/tembus-rp-75-triliun-devisa-negara-daripariwisata-tahun-2011, accessed on May 9, 2012. Republika, “Devisa Pariwisata Ditarget 9 Miliar Dolar AS”, http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/01/24/lyb7as-devisa-pariwisataditarget-9-miliar-dolar-as, accessed on May 9, 2012. DISSERTATION Siti Mariyam, Pergeseran Kebijakan Dalam Pelayanan Publik Pada badan usaha milik negara (BUMN) (Dalam Perspektif Hukum dan Kebijaksanaan Publik), Thesis, Post Gradiation Program of Dipponegoro University, Semarang, 2007. 213 ... PENGUASAAN HOTEL ATAS PANTAI DI BALI (TINJAUAN EKO-YURIDIS TERHADAP PEMBANGUNAN HOTEL YANG MELEWATI SEMPADAN PANTAI) Tjok Istri Sri Harwathy, Made Emy Andayani Citra, Ni Luh Gede Yogi Arthani,dan Dewi Bunga Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar [email protected] Abstract: The coastal is owned by the state property that can be used by anyone. Coastals are public places, not the property of the hotel. Mastery of the coastal by the hotel is a violation of the rights of both the tourists as well as indigenous peoples. Travelers who are not hotel guests are prohibited to enter the coastal territory. Violations of the rights of indigenous peoples can be seen from the limited opportunities for indigenous people to carry out religious ceremonies on the coastal. To overcome these problems the government should issue a policy that ordered the hotel to open the access road to the coastal and supervise the construction of hotel licensing. Key Words: Mastery, hotels, coastals, community rights. Pendahuluan Pembangunan hotel di kawasan pantai di Bali semakin berkembang pesat. Hotel merupakan salah satu sarana akomodasi yang sangat penting dalam pembangunan industri pariwisata, terlebih lagi bagi Bali yang menjadi pusat industri pariwisata di Indonesia. Di daerah pariwisata seperti Kuta, Sanur, Nusa Dua dan Petitenget dibangun hotel-hotel tepat di depan pantai. Pemandangan pantai menjadi daya tarik yang disajikan oleh pengusaha perhotelan untuk menjaring tamu hotel. Begitu tamu hotel membuka jendela maka ia langsung dapat melihat keindahan pantai. Hal ini membuat pengusaha hotel membangun sarana akomodasi tersebut semakin dekat dengan pantai. Bahkan beberapa diantaranya justru melewati sempadan pantai. Bangunan Restoran Garfu milik Hotel Rama Candidasa dinilai melanggar sempadan pantai oleh DPRD Karangasem. Guna menegakkan peraturan terutama Perda No. 8 tahun 2003 tentang sempadan pantai, DPRD Karangsem minta bangunan restoran itu dibongkar. 108 Kasus penguasaan pantai juga terjadi dalam proyek hotel Mulia Graha di Bali. Tim penyidik Satpol PP Provinsi Bali telah melakukan sidak ke lokasi proyek Hotel Mulia Graha, di seputar pantai Geger, Desa Pemingge, Kuta Selatan. Tim ingin memastikan adanya pelanggaran perda 108 Bali Post, “Langgar Sempadan Pantai, http://www.balipost.co.id/BaliPostcetak/2007/1/6/b12.htm DPRD Minta Restoran Garfu Dibongkar”, 214 ... (peraturan daerah). Pelanggaran yang dimaksud adalah adanya kemungkinan pelanggaran sempadan pantai yakni berjarak 100 meter dari air pasang tertinggi sesuai RTRW Bali. 109 Pantai adalah suatu wilayah perbatasan antara wilayah daratan dengan wilayah perairan. Kawasan sempadan pantai adalah kawasan yang memang sengaja dibuat di sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai, keselamatan bangunan, dan ketersediaan ruang untuk publik. Menurut Materi Teknis RTRWP Bali, 2009-2029, luas sempadan pantai sebagai kawasan lindung Bali pada tahun 2029 adalah 6.289,00 ha atau 1,12% dari total luas wilayah Bali. Kawasan sempadan pantai juga menjadi kawasan suci pantai bagi umat Hindu yang ada di Bali. Oleh sebab itu, kawasan sempadan pantai harus dipertahankan dan dilindungi dari penguasaan pengusaha. Pembangunan hotel-hotel di Bali yang melewati sempadan pantai dengan sendirinya membawa dampak negatif bagi ekologi pantai. Keberadaan bangunan yang melewati sempadan pantai bertendensi memudahkan abrasi. Kondisi ini juga mengancam kelestarian lingkungan hidup yang ada di pantai. Selain berdampak negatif terhadap ekologi lingkungan, pembangunan hotel yang melewati sempadan pantai juga mempersempit akses bagi masyarakat untuk masuk dan menikmati keindahan pantai. Pantai seolah-olah menjadi milik hotel yang hanya dapat dinikmati oleh tamu hotel, sementara masyarakat umum dilarang untuk masuk ke wilayah pantai di depan hotel. Secara umum, keberadaan hotel yang melewati sempadan pantai ini juga menutup akses bagi nelayan untuk merapatkan perahunya ke pantai. Hal ini tentu akan berdampak pada sempitnya wilayah pemancingan (fishing ground). Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tinjauan Yuridis Penguasaan Pantai oleh Hotel di Bali Pantai adalah sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara. Hal ini membawa konsekuensi yuridis pada konsep penguasaan atas pantai yakni siapa yang berkuasa atas pantai. Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 disebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Beranjak pada rumusan normatif ini maka jelas bahwa pantai adalah suatu wilayah yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sehingga pengusaha hotel tidak berhak dan tidak berwenang untuk menguasai pantai. Pada prinsipnya, kekuasaan menunjukkan beberapa hal penting yakni: 109 Berita Dewata, “Satpol PP Bali Sidak Hotel Buronan http://beritadewata.com/Sosial_Politik/Sosial/Satpol_PP_Bali_Sidak_Hotel_Buronan_BLBI.html BLBI”, ... 215 a. Setiap kekuasaan wajib dipertanggungjawabkan. b. Setiap pemberian kekuasaan, harus dipikirkan beban tanggung jawab untuk setiap penerima kekuasaan. c. Kesediaan untuk melaksanakan tanggung jawab harus secara inklusif sudah diterima pada saat menerima kekuasaan. d. Tiap kekuasaan ditentukan batas kewenangan dan sekaligus beban tanggung jawab. e. Kewenangan dan beban tanggung jawab ditentukan oleh bentuk dan struktur organisasi. 110 Negara sebagai satu-satunya pihak yang memiliki kekuasaan atas pantai, bertanggung jawab untuk mencegah dan menegakkan hukum terhadap setiap indikasi dan perbuatan yang menjurus pada penguasaan pantai oleh suatu golongan tertentu. Salah satu indikator dalam mendeteksi adanya upaya-upaya penguasaan pantai oleh hotel adalah adanya pembangunan hotel yang melewati garis sempadan pantai. Dalam Pasal 1 angka 44 Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 ditentukan bahwa yang dimaksud dengan Sempadan Pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan ketersediaan ruang untuk lalu lintas umum. Sempadan pantai memiliki fungsi baik bagi lingkungan pantai, bagi keberadaan hotel dan juga bagi masyarakat. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 44 Ayat (13) Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kawasan sempadan pantai adalah kawasan sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai, keselamatan bangunan, dan ketersediaan ruang untuk publik. Pengecualian lebar sempadan pantai untuk pantai-pantai yang ada di Daerah Bali setelah mendapat kajian teknis dari instansi dan atau pakar terkait. Kajian teknis dimaksud meliputi daya dukung fisik alam lingkungan pantai yang sekurangkurangnya meliputi tinjauan geologi, geologi tata lingkungan, kemungkinan erosi dan abrasi, pengaruh hidrologi lokal dan regional, dan rencana pemanfaatan kawasan pantai. Penetapan sempadan pantai pada bangun-bangunan di luar kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan disamakan dengan penetapan sempadan pantai di kawasan perdesaan. Untuk melindungi lingkungan hidup di pantai, maka pemerintah provinsi Bali menentukan bahwa disebutkan bahwa sebaran kawasan sempadan pantai terletak pada 110 Ibrahim, “Status Hukum Internasional Perjanjian Internasional Dalam Hukum Nasional: Permasalahan Teoritik dan Praktek”, disajikan dalam lokakarya Evaluasi UU No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional pada 18 Oktober 2009, Grup Riset Otonomi Daerah Universitas Udayana, Denpasar, 2010. ... 216 sepanjang 610,4 (enam ratus sepuluh koma empat) km garis pantai wilayah. Kawasan ini dikategorikan sebagai kawasan perlindungan setempat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 ayat (13) Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029. Dalam Pasal 50 ayat (4) peraturan daerah ini dinyatakan bahwa Sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan kriteria: a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai; dan c. Gubernur menetapkan pedoman penyelenggaraan penanggulangan abrasi, sedimentasi, produktivitas lahan pada daerah pesisir pantai lintas kabupaten/ kota. Pengaturan mengenai sempadan pantai ini merupakan instrumen preventif dalam menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat di sekitar pantai. Perhatian akan pentingnya lingkungan hidup yang baik dan sehat ditandai dengan munculnya disiplin ilmu hukum lingkungan. Hukum lingkungan merupakan bidang ilmu yang masih muda yang perkembangannya baru terjadi pada dua dasawarsa terakhir ini. Apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek lingkungan, maka panjang atau pendeknya sejarah tentang peraturan tersebut tergantung daripada apa yang dipandang sebagai “environmental concern” (perhatian terhadap lingkungan). 111 Perlindungan lingkungan pantai ini dilakukan dengan keluarnya berbagai kebijakan hukum tentang pembangunan di sekitar pantai. Dalam Pasal 108 ayat 3 Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 ditentukan bahwa Arahan peraturan zonasi sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) huruf c, mencakup: a. pengaturan jarak sempadan pantai sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4); b. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; c. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi; d. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan dan kegiatan pelabuhan; e. pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf d; f. pengamanan sempadan pantai sebagai ruang publik; g. pengamanan dan perlindungan lokasi tertentu di kawasan sempadan pantai yang berfungsi sebagai tempat melasti; 111 36. Koesnadi Hardjasoemantri, 1999, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada Press, Yogyakarta, hal. ... h. i. j. k. 217 pemanfaatan untuk penambatan perahu nelayan; pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan; pantai yang berbentuk jurang, memanfaatkan aturan zonasi sempadan jurang; dan pantai yang berbentuk hutan bakau, memanfaatkan aturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau. Pembangunan industri pariwisata termasuk bidang usaha perhotelan yang berwawasan lingkungan wajib dikembangkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat 4 UUD 1945. Pasal tersebut menyatakan “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Ketentuan ini dimaknai dalam dua prinsip yakni prinsip pembangunan berkelanjutan dan keharusan adanya wawasan lingkungan hidup bersifat mutlak. Kedua prinsip tersebut harus ada dalam setiap pemikiran dan perumusan kebijakan pembangunan, baik kebijakan pembangunan nasional, kebijakan pembangunan regional, maupun kebijakan pembangunan daerah provinsi dan pembangunan kebijakan daerah kabupaten/ kota di seluruh Indonesia. Konsekuensinya, semua pihak terutama para pejabat yang bertanggung jawab dalam urusan perencanaan pembangunan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan harus mengubah cara berpikirnya menjadi berwawasan lingkungan. 112 Dengan demikian setiap pihak harus bekerja sama dalam pengaturan pembangunan hotel agar jangan sampai nmerusak lingkungan. Pelanggaran Hak Masyarakat Kawasan pantai merupakan kawasan yang dilindungi oleh pemerintah. Dalam melindungi kawasan ini, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang sempadan pantai sebagai garis batas yang berfungsi sebagai kawasan perlindungan. Penguasaan hotel atas pantai melalui pembangunan hotel yang melewati sempadan pantai merupakan pelanggaran terhadap hak masyarakat. Pelanggaran ini menyangkut pelanggaran hak atas lingkungan hidup, pelanggaran hak untuk berekreasi ke pantai bagi masyarakat umum, pelanggaran hak untuk melaksanakan upacara keagamaan dan pelanggaran hak untuk dapat bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak khusus bagi nelayan. Pembuatan sempadan pantai bertujuan untuk mencegah abrasi, terlebih bagi Bali yang sangat rentan dengan abrasi 113 dan berpotensi tsunami. Penguasaan hotel atas pantai melalui 112 Jimly Asshiddiqie, 2010, Green Constitution Nuansa Hijau Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 152. 113 Abrasi pantai di Indonesia, telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Sedikitnya 40 prosen dari 81 ribu km pantai di Indonesia, rusak akibat abrasi. Dalam beberapa tahun terakhir, garis pantai di ... 218 pembangunan hotel yang melewati sempadan pantai berpotensi menimbulkan abrasi yang semakin besar. Wilayah Bali merupakan wilayah yang rentan akan abrasi. Penyebab abrasi yang paling dominan adalah akibat terjadinya pelanggaran sempadan pantai dan tergerusnya struktur tanah di daerah pesisir sehingga air laut mudah masuk ke daratan.114 Hal ini bukan hanya berbahaya bagi lingkungan namun juga berbahaya bagi keberadaan infrastruktur hotel tersebut. Ancaman abrasi akibat penguasaan hotel atas pantai ini merupakan pelanggaran atas hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh negara. Hak konstitusional ini diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Selanjutnya Siti Sundari Rangkuti menyebutkan bahwa lingkungan sudah merupakan milik bersama (public property) sehingga tidak seorang pun diperkenankan mencemarkannya. 115 Penguasaan pantai oleh hotel dengan sendirinya melanggar hak masyarakat untuk menikmati dan berekreasi di pantai. Pengusaha yang telah mendapatkan izin pembangunan hotel di depan pantai berasumsi bahwa pantai tersebut adalah milik hotel sehingga yang dapat menikmati hotel hanya tamu yang menginap di hotel bersangkutan. Pihak hotel tidak segan-segan menegur pengunjung pantai yang duduk-duduk di pantai yang “dikuasai” oleh hotel, sehingga ada ungkapan di masyarakat “orang Bali sulit masuk Bali.” Padahal pantai merupakan ruang publik yang artinya boleh dinikmati oleh siapa saja sepanjang mereka tidak merusak pantai. Eksploitasi ekonomi ini tentu saja telah melanggar hak masyarakat. Tertutupnya akses pantai bagi masyarakat, telah melanggar hak masyarakat untuk melaksanakan upacara keagamaan. Umat Hindu di Bali memiliki keyakinan bahwa pantai merupakan kawasan suci sehingga banyak upacara keagamaan yang dilakukan di pantai beberapa daerah di Indonesia mengalami penyempitan yang cukup memprihatinkan. Abrasi yang terjadi mampu menenggelamkan daratan antara 2 hingga 10 meter pertahun. Dampak yang diakibatkan oleh abrasi ini sangat besar. Garis pantai akan semakin menyempit dan apabila tidak diatasi lama kelamaan daerah-daerah yang permukaannya rendah akan tenggelam. Pantai yang indah dan menjadi tujuan wisata menjadi rusak. Pemukiman warga dan tambak tergerus hingga menjadi laut. Tidak sedikit warga di pesisir pantai yang telah direlokasi gara-gara abrasi pantai ini. Abrasi pantai juga berpotensi menenggelamkan beberapa pulau kecil di perairan Indonesia. Anonim, “Abrasi Rusak 40 Prosen Pantai Indonesia”, http://alamendahal. wordpress.com/2009/11/09/abrasi-rusak-40-prosen-pantai-indonesia/ 114 Dewa Putu Sumerta, “8 Pantai di Bali Abrasi”, http://nasional.inilahal. com/read/detail/1849197/8pantai-di-bali-abrasi. 115 Siti Sundari Rangkuti, 2000, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional Edisi Kedua, Airlanggga University Press, Surabaya, hal. 14-15. ... 219 seperti upacara melasti, rangkaian upacara ngaben dan lain-lain. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 dinyatakan bahwa pengamanan dan perlindungan lokasi tertentu di kawasan sempadan pantai yang berfungsi sebagai tempat melasti. Arahan pengelolaan kawasan suci pantai disetarakan dengan kawasan sempadan pantai. Pantai merupakan pusat kegiatan nelayan, kegiatan pelabuhan dan penambatan perahu nelayan. Penguasaan pantai oleh hotel telah melanggar hak nelayan untuk bekerja. Apalagi jika lingkungan pantai tersebut sudah rusak akibat adanya penguasaan hotel. Nelayan sebagai komunitas terbesar di pantai ini tidak dapat lagi dapat menambatkan perahunya di pantai karena tidak diizinkan oleh pihak hotel atau dianggap merusak pemandangan pantai. Akibatnya nelayan harus mencari “lahan” baru untuk melakukan kegiatan mencari ikan. Penguasaan pantai oleh pihak hotel yang berakibat pada pelanggaran hak masyarakat merupakan bentuk konkrit dari kegagalan pemerintah dalam menjaga kawasan pantai. Mas Achmad Santosa menganalisis bahwa kegagalan tersebut sebagai “ketidakmampuan para penentu kebijakan untuk mengintegrasikan ketiga pilar pembangunan berkelanjutan (ekologi, ekonomi, sosial budaya) dan ketiga pilar tersebut dengan good governance ke dalam proses pengambilan keputusan kebijakan negara” 116 Pembangunan ekonomi pariwisata harus berorientasi pada perlindungan lingkungan hidup dan selaras dengan kehidupan sosial masyarakat bersangkutan. Upaya Penanggulangan Melalui Instrumen Hukum Pengakuan hak manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, secara normatif menimbulkan 2 (dua) dimensi hukum. Pertama, pemerintah berarti mengakui bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak dasar yang harus mendapat perlindungan dari semua pihak. Khususnya bagi Pemerintah, bentuk perlindungan yang dapat diberikan terhadap hak ini adalah memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengambil bagian dalam prosedur administratif seperti berperan serta atau hak banding terhadap penetapan administratif. Kedua, merupakan bentuk perlindungan ekstensif (luas) terhadap hak-hak perseorangan, sehingga dapat memberikan landasan gugatan hukum atau hak menuntut kepada setiap orang yang merasa haknya atas lingkungan hidup yang hidup dan sehat diganggu pihak lain. 117 116 Mas Achmad Santosa, Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan, Makalah, Training Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Eksekutif, Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta, 2004, hal. 3 117 I Made Arya Utama, 2007, Hukum Lingkungan Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Pustaka Sutra, Bandung, hal. 141. ... 220 Hak atas lingkungan yang baik dan sehat adalah hak subjektif dari warga negara. Heinhard Steiger dengan tulisan “The Fundamental Right to a Decent Environment” dalam “Trends in Environmental Policy and Law” menyatakan bahwa “apa yang dinamakan hak-hak subjektif (subjective right) adalah bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang”.118 Dengan hak-hak subjektif tersebut akan diberikan kepada yang mempunyainya suatu tuntutan yang sah guna meminta kepentingannya akan suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat itu dihormati, suatu tuntutan yang dapat didukung oleh prosedur hukum, dengan perlindungan hukum oleh pengadilan dan perangkat-perangkat lainnya. Tuntutan tersebut mempunyai 2 (dua) fungsi yang berbeda, yaitu fungsi pertama, adalah yang dikaitkan pada hak membela diri terhadap gangguan dari luar yang menimbulkan kerugian pada lingkungannya, sedangkan fungsi yang kedua dikaitkan pada hak menuntut dilakukannya sesuatu tindakan agar lingkungannya dapat dilestarikan, dipulihkan atau diperbaiki. Konsekuensi kepemilikan hak atas lingkungan hidup tersebut adalah kewajiban pemerintah dalam mengeluarkan regulasi dan melaksanakan penegakan hukum serta hak masyarakat untuk mengajukan tuntutan atas penguasaan pantai oleh hotel. Hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat. 119 Oleh sebab itu instrumen hukum menjadi salah satu upaya untuk mengembalikan hak-hak masyarakat atas pantai. Penggunaan instrumen hukum tersebut dimulai dari aktivasi instrumen prenventif yakni dengan memperketat perizinan hotel. Dalam upaya pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup setiap usaha wajib memiliki amdal atau Upaya Pengelolaan lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup yang sudah direkomendasikan berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dalam hal ini penilaian tersebut berupa keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya. Adapun yang dimaksud dengan AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 11). 118 Rachmadi Usman, 2003, Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 75. 119 Satjipto Raharjo, 1996, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal. 189 ... 221 UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelanggaraan usaha dan/atau kegiatan (Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 1 angka 11). Upaya Pengelolaan lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah salah satu instrumen pengelolaan lingkungan yang merupakan salah satu persyaratan perijinan bagi pemrakarsa yang akan melaksanakan suatu usaha/kegiatan di berbagai sektor. Dalam mengeluarkan izin lingkungan ini maka pemerintah daerah harus benar-benar meneliti peta pembangunan dari hotel yang akan dibangun tersebut agar jangan sampai melewati garis sempadan pantai. Pemanfaatan pantai bagi seluruh masyarakat merupakan perlindungan hukum bagi masyarakat. Adanya perlindungan hukum bagi masyarakat disamping sebagai suatu urgensi yang wajar dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran juga merupakan conditio sine qua non dalam penegakan hukum. 120 Penegakan hukum sebagai instrumen hukum represif terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidahkaidah yang mantap, mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian hidup. 121 Penegakan hukum dilakukan dengan pemberian sanksi bagi hotel yang menguasai pantai. Pemberian sanksi kepada pihak hotel didasarkan pada karakteristik hukum lingkungan yang holistik. Hukum lingkungan mencakup aturan-aturan hukum administrasi, hukum perdata, hukum pidana dan hukum internasional sepanjang aturan-aturan itu mengenai upaya pengelolaan lingkungan hidup. Pencakupan beberapa bidang hukum ke dalam hukum lingkungan berdasarkan pemikiran para pakar ekologi, bahwa “masalah lingkungan harus dilihat dan diselesaikan berdasarkan pendekatan menyeluruh dan terpadu.” 122 Dengan demikian sanksi hukum yang dapat dijatuhkan adalah sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Instrumen preventif hendaknya selalu diutamakan dalam mengembalikan hak-hak masyarakat sebab instrumen ini merupakan upaya pencegahan sehingga dalam penggunaannya akan menelan biaya yang lebih kecil dari pelaksanaan penegakan hukum. Ketika hotel telah beroperasi dan pemerintah baru menegakkan hukum dan mengancam 120 Sjachran Basah, 1992, Hukum acara Pengadilan Dalam lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA), Rajawali Press, Jakarta, hal 4-5. 121 Soerjono Soekanto, 2004, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan ke-5, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 5. 122 Takdir Rahmadi dan Munadjat Danusaputro, 1981, Hukum Lingkungan, Buku I Umum, Binacipta, Bandung, hal. 36 222 ... dengan pencabutan izin maka pihak hotel akan menggunakan tenaga kerjanya sebagai perisai. Dengan alasan bahwa akan banyak tenaga kerja yang di PHK, maka pemerintah akan lebih lunak dalam menegakkan hukum. Pembongkaran bangunan juga membutuhkan biaya yang besar baik bagi pemilik hotel yang sudah menginvestasikan modalnya maupun bagi pemerintah yang membongkar bangunan. Oleh sebab itu diperlukan pengawasan yang intensif terhadap setiap pembangunan hotel. Pengawasan ini dapat dilakukan dengan pola kemitraan yang melibatkan asosiasi pengusaha pariwisata dan masyarakat. Penutup Secara yuridis, hotel tidak memiliki hak untuk menguasai pantai. Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 disebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Pantai adalah kekayaan yang dimiliki oleh negara yang dapat dimanfaatkan oleh siapa pun sehingga pantai adalah tempat umum bukan milik hotel. Pelanggaran ini menyangkut pelanggaran hak atas lingkungan hidup, pelanggaran hak untuk berekreasi ke pantai bagi masyarakat umum, pelanggaran hak untuk melaksanakan upacara keagamaan dan pelanggaran hak untuk dapat bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak khusus bagi nelayan. Dalam upaya mengembalikan hak-hak masyarakat yang dilanggar akibat adanya pembangunan hotel yang melewati sempadan pantai maka dipergunakan instrumen hukum. Instrumen hukum tersebut meliputi instrumen hukum preventif berupa izin lingkungan dan instrumen hukum represif melalui penegakan hukum. Instrumen hukum preventif hendaknya diutamakan permasalahan tersebut daripada maka instrumen pemerintah hukum harus preventif. mengeluarkan Untuk mengatasi kebijakan yang memerintahkan hotel untuk membuka akses jalan menuju pantai dan tidak lagi mengeluarkan izin pembangunan hotel yang menguasai pantai. DAFTAR PUSTAKA BUKU Arya Utama, I Made, 2007, Hukum Lingkungan Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Pustaka Sutra, Bandung. Jimly Asshiddiqie, 2010, Green Constitution Nuansa Hijau Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Koesnadi Hardjasoemantri, 1999, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada Press, Yogyakarta. ... 223 Rachmadi Usman, 2003, Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Satjipto Raharjo, 1996, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung. Siti Sundari Rangkuti, 2000, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional Edisi Kedua, Airlanggga University Press, Surabaya. Sjachran Basah, 1992, Hukum acara Pengadilan Dalam lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA), Rajawali Press, Jakarta. Soerjono Soekanto, 2004, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan ke-5, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Takdir Rahmadi dan Munadjat Danusaputro, 1981, Hukum Lingkungan, Buku I Umum, Binacipta, Bandung. MAKALAH Ibrahim, “Status Hukum Internasional Perjanjian Internasional Dalam Hukum Nasional: Permasalahan Teoritik dan Praktek”, disajikan dalam lokakarya Evaluasi UU No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional pada 18 Oktober 2009, Grup Riset Otonomi Daerah Universitas Udayana, Denpasar, 2010. Mas Achmad Santosa, Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan, Makalah, Training Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Eksekutif, Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta, 2004. INTERNET Anonim, “Abrasi Rusak 40 Prosen Pantai Indonesia”, http://alamendah.wordpress.com/2009/11/09/abrasi-rusak-40-prosen-pantai-indonesia/ Bali Post, “Langgar Sempadan Pantai, DPRD Minta Restoran Garfu Dibongkar”, http://www.balipost.co.id/BaliPostcetak/2007/1/6/b12.htm Berita Dewata, “Satpol PP Bali Sidak Hotel Buronan BLBI”, http://beritadewata.com/Sosial_Politik/Sosial/Satpol_PP_Bali_Sidak_Hotel_Buronan_ BLBI.html Sumerta, Dewa Putu “8 Pantai di Bali http://nasional.inilah.com/read/detail/1849197/8-pantai-di-bali-abrasi. Abrasi”, SUMBER HUKUM Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029. ... 224 URGENSI NASKAH AKADEMIK DALAM PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-PERUNDANGAN Agung Dwi Astika Astika & Associates [email protected] Abstract: Implementation of the general welfare by establishing various laws and regulations is the duty of the State. In fact a lot of legislation that can not be implemented optimally. There are also some products of legislation that was canceled by the minister in the country because of conflict with the Constitution. Preparation of legislation that would bring terrible loss of time, cost and effort. Under the provisions of Act No 12 of 2011 on the Establishment of Legislation clearly states that academic texts is something that must exist in the making of legislation both both at central level or at regional level. Academic texts can be regarded as “public space” that allows the aspirations of the people accommodated in the preparation of the substance of legislation. With academic texts, the public spaces (society) is very open. The society can convey their aspirations and also give the appreciation toward the substance of legislation that will and are being regulated. Key words: legislation, academic text, society. Pendahuluan Sejak awal berdirinya Negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 telah menegaskan bahwa Negara Indonesia didasarkan atas hukum, hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD RI 1945) pada bagian penjelasannya, Pengakuan Indonesia sebagai negara hukum kembali mendapatkan menegasan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 UUD RI 1945 hasil amendemen ke tiga. Negara hukum yang di tetapkan dalam UUD RI 1945 merupakan negara hukum dalam arti Negara Pengurus, sebagaimana tertulis dalam alenia 4 pembukaan UUD RI 1945 yang berbunyi 123 ; “ … Untuk membentuk sutu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memahukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social…” Guna mengemban tugas negara dalam penyelenggaraan kesejahteraan umum tersebut pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting, oleh karena campur tangan negara dalam mengurusi kesejahteraan rakyat bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan dengan membentuk peraturan perundang-undangan tidak mungkin di hindarkan. 123 Maria Farida Indriati S., 2007, Ilmu Perundang-Undangan 1, Kanisius, Yogyakarta, hal. 1 ... 225 Akan tetapi dalam kenyataan walaupun peraturan perundang-undangan telah banyak dibuat baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, akan tetapi masih banyak yang tidak dapat diterapkan secara maksimal sebagai contoh Uu No 22 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas terdahulu, sampai sekarang tidak dapat dijalankan secara maksimal, bahkan banyak perda oleh mendagri yang dibatalkan kurang lebih 400 perda diseluruh Indonesia karena dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai negara hukum dan demokrasi, belum lagi berkaitan dengan banyaknya undang –undang yang diuji materiilkan ke mahkamah konstitusi, fakta-fakta ini tidak dapat memungkiri buruknya peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat sampai ke daerah, baik dari segi substansi maupun tatacara pembuatannya. Selain pembatalan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun ketidak efektifan pemberlakuan undang-undang yang telah dibuat, pembuatan peraturan perundangundangan yang buruk tentunya membawa dampak kerugian yang besar pada negara terutamanya dari segi waktu, biaya dan tenaga untuk menyelesaiakan peraturan perundangundangan tersebut. Khususnya dari segi biaya seharusnya biaya pembuatan peraturan perundang-undangan yang besar bisa dipergunakan untuk membiayai pembangunan yang lain sehingga kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan. Menghindari kerugian yang lebih besar dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, maka perlu dibuat peraturan perundangundangan yang sesuai dengan dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan, selain itu dari segi substansi maka harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang- undangan pada dasarnya harus sesuai dengan beberapa aspek, antara lain aspek sosiologis, aspek filosofis dan aspek yuridis. Guna mengetahui aspek-aspek tersebut haruslah dilakukan pengkajian dan penelitian yang dituangkan dalam naskah akademik. Kedudukan naskah akademik dalam pembuatan peraturan perundang-undangan sangat menarik untuk di bahas dalam tulisan ini. Pengertian Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan Di dalam ilmu perundang-undangan, naskah akademik merupakan prasyarat untuk menyusun rancangan peraturan perundang-undangan 124. Pemakaian istilah Naskah Akademik peraturan perundang-undangan secara baku digulirkan tahun 1994 melalui Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) No. G.159.PR.09.10 tahun 124 Aan Eko Widiarto, “Metode dan Teknik Penyusunan Naskah Akademik ”, makalah. ... 226 1994 tentang petunjuk teknis penyusunan naskah akademik peraturan perundang-undangan, dikemukakan bahwa naskah akademik peraturan perundang-undangan adalah naskah awal yang memuat pengaturan materi-materi perundang-undangan bidang tertentu yang telah ditinjau secara sistemik, holistik dan futuristik. Sebelumnya berbagai istilah mengenai naskah akademik peraturan perundangundangan ini bermunculan, seperti istilah naskah rancangan undang-undang, naskah ilmiah rancangan undang-undang, rancangan ilmiah peraturan perundang-undangan, naskah akademis rancangan undang-undang, academic draft penyusunan peraturan perundangundangan 125. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2005 tentang tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dalam Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa : ”Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan rancangan undang-undang.” Di dalam Pasal 5 ayat 1 Perpres Nomor 68 Tahun 2005 menyebutkan : ”Pemrakarsa dalam menyusun rancangan undang-undang dapat terlebih dahulu menyusun naskah akademik mengenai materi yang akan diatur dalam rancangan undang-undang” Pasal 5 ayat 2 Perpres Nomor 68 Tahun 2005 menyebutkan : ”Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemrakarsa bersama-sama dengan departemen yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya dapat diserahkan kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian untuk itu.” Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang menyebutkan istilah Naskah Akademik disebut dengan Rancangan Akademik. Dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan : ”Menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa penyusunan rancangan undang-undang dapat pula terlebih dahulu menyusun rancangan akademik mengenai rancangan undang-undang yang akan disusun.” Namun dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebelumnya, secara eksplisit tidak mengatur mengenai Naskah Akademik sebelum penyusunan suatu peraturan perundang-undangan. Namun, di 125 Abdul Wahid, “Penyusunan Naskah Akademik”, makalah, www.legalitas.org ... 227 dalam Undang-Undang tersebut disebutkan mengenai keterlibatan pihak lain di luar lembaga legislatif dan eksekutif dalam penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini disebut dengan partisipasi masyarakat. Pasal 53 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 menyebutkan : ”Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah.” Dalam hal ini partisipasi masyarakat dalam penyusunan sebuah peraturan perundangundangan bisa diinterpretasikan sebagai bentuk keterlibatan masyarakat yang wujud nyatanya berupa penyusunan Naskah Akademik. Dengan tidak ”diaturnya” naskah akademik secara eksplisit di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tersebut, maka ketentuan Keppres Nomor 188 Tahun 1998 Pasal 3 ayat (1) masih berlaku. Hal itu dikarenakan, dalam Pasal 57 huruf c Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 ditentukan bahwa peraturan perundang-undangan lain yang ketentuannya telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku. Akibat Naskah Akademik tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, maka ketentuan yang mengatur Naskah Akademik di dalam Keppres Nomor 188 Tahun 1998 tetap berlaku 126. Menurut Aan Eko Widiarto dalam makalahnya tentang Naskah Akademik Sebagai Pendukung Pembentukan rancangan Produk Perundang-undangan Daerah, mengatakan bahwa naskah akademik dapat diartikan sebagai konsepsi pengaturan suatu masalah (obyek perundang-undangan) secara teoritis dan sosiologis. Naskah Akademik secara teoritik mengakaji dasar filosofis, dasar yuridis dan dasar politis suatu masalah yang akan diatur sehingga mempunyai landasan pengaturan yang kuat 127. Menurut Harry Alexander dalam bukunya Panduan Perancangan Perda di Indonesia, memberikan definisi tentang Naskah Akademik bahwa Naskah Akademik adalah naskah awal yang memuat gagasan-gagasan pengaturan dan materi muatan perundang-undangan bidang tertentu disebut Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan 128 Definisi lainnya dari sebuah naskah akademik, dikemukakan oleh Jazim Hamidi 129 bahwa naskah akademik ialah naskah atau uraian yang berisi penjelasan tentang : 126 Aan Eko Widiarto, op. cit., hal. 5 Mahendra Putra Kurnia dkk, Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif ( Urgensi, Strategi, dan Proses Bagi Pembentukan Perda yang baik ), Kreasi Total Media (KTM), Yogyakarta, cetakan pertama, Juni 2007, hal. 30 128 Ibid. 129 Ibid., hal. 30-31 127 ... a. b. c. d. 228 Perlunya sebuah peraturan harus dibuat; Tujuan dan kegunaan dari peraturan yang akan dibuat; Materi-materi yang harus diatur peraturan tersebut; Aspek-aspek teknis penyusunan; Naskah Akademik paling sedikit memuat dasar filosofis, sosiologis, yuridis, pokok dan lingkup materi yang diatur. Dasar filosofis merupakan landasan filsafat atau pandangan yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan suatu masalah ke dalam peraturan perundang-undangan. Dasar yuridis ialah ketentuan hukum yang menjadi dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan. Dasar sosiologis, naskah akademik disusun dengan mengkaji realitas masyarakat yang meliputi kebutuhan hukum masyarakat, aspek sosial ekonomi dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang (rasa keadilan masyarakat). Selanjutnya dalam Undang- Undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 jelas mencantumkan “Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan UndangUndang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat” Urgensi Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan ketentuang UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jelas menyebutkan bahwa naskah akademik merupakan sesuatu yang in heren dalam pembuatan peraturan perundang-undangan baik ditingkat pusat sampaii ketingkat daerah, hal mana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal-pasal sebagai berikut : Pasal 19 (1) Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memuat program pembentukan Undang-Undang dengan judul Rancangan Undang-Undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. (2) Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Undang-Undang yang meliputi: a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan c. jangkauan dan arah pengaturan. (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik. Kata “dituangkan “ yang terdapat dalam Pasal 3 diatas dapat diartikan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pada tahap perencanaan pembuatan undang- ... 229 undang naskah akademik haruslah selalu dibuat terlebih dahulu, karena dalam naskah akademik tersebut harus dituangkan materi-materi yang diatur dalam Pasal 2 sebelumnya yaitu tentang : latar belakang dan tujuan penyusunan; sasaran yang ingin diwujudkan; dan jangkauan dan arah pengaturan. Bagian terpenting dari materi tersebut haruslah telah melalui pengkajian dan penyelarasan. Adapun yang dimaksud dengan “pengkajian dan penyelarasan” adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang vertical atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan, sebagaimana penjelasan Pasal 3. Dengan demikian pembuatan naskah akademis adalah mutlak . Keharusan membuat naskah akademis juga diberlakukan dalam pembuatan perda propinsi dan kabupaten sebagaimana tertuang dalam ketentuan Undang-undang no 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut : Pasal 33 (1) Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan judul Rancangan peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. (2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang meliputi: a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan dan arah pengaturan. (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik. Pasal 40 Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sebelum ditetapkannya Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan penyusunan naskah akademik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia masih bersifat fakultatif (bukan keharusan). Hal ini bisa dilihat di dalam Pasal 3 ayat (1) Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, di mana disebutkan bahwa : ”Menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa penyusunan rancangan undang-undang dapat pula terlebih dahulu menyusun rancangan akademik mengenai rancangan undangundang yang akan disusun.” ... 230 Penggunanan rumusan ”dapat pula” tersebut mengandung makna tidak harus, sehingga Menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa penyusunan rancangan undangundang dapat tidak menyusun naskah akademik. Selain itu dalam Pasal 3 ayat (1) tersebut hanya diatur penyusunan naskah akademik untuk rancangan undang-undang sehingga beberapa jenis peraturan perundang-undangan yang lain seperti Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Pemerintah PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), tidak terikat ketentuan Pasal tersebut. Dalam konteks otonomi daerah, amandemen UUD 1945 juga memberikan peluang yuridis bagi daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga menentukan keleluasaan yang besar bagi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Kewenangan yang luas tersebut tentunya harus dipahami untuk menuju kesejahteraan dan keadilan sosial bersama sehingga produk perundang-undangan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian untuk kepentingan masyarakat maka masyarakat harus diajak bersama-sama dalam merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan di daerah, tanpa mengesampingkan keberadaan wakil-wakil rakyat di DPRD. Perlu adanya kesinambungan peran antara masyrakat dengan DPRD karena pada kenyataannya wakil-wakil rakyat di DPRD belum (tidak mampu) mewakili seluruh aspirasi masyarakat yang sangat dinamis. Sehingga diperlukan kearifan bersama baik Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat dalam membuat peraturan perundang-undangan di daerah dengan menyusun naskah akademik sebelum merancang peraturan daerah. Fungsi naskah akademik menurut Harry Alexander, seperti yang dikutip oleh Mahendra Putra Kurnia dkk, dalam bukunya Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif, mengatakan bahwa kedudukan naskah akademik merupakan : a. bahan awal yang memuat gagasan-gagasan tentang urgensi, pendekatan, luas lingkup dan materi muatan suatu peraturan daerah; b. Bahan petimbangan yang dipergunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan Raperda/Rancangan Produk Hukum Daerah lainnya kepada Kepala Daerah; c. Bahan dasar bagi penyusunan Raperda /Rancangan Produk Hukum Daerah lainnya; Menurut Sony Maulana S, 130 yang dengan menggunakan istilah Rancangan Akademik mengemukakan, terdapat 3 (tiga) fungsi dari Rancangan Akademik, yaitu : 130 Mahendra Putra Kurnia dkk., op. cit., hal. 31 ... 231 a. Menginformasikan bahwa perancang telah mempertimbangkan berbagai fakta dalam penulisan Rancangan Peraturan Daerah; b. Memastikan bahwa perancang menyusun fakta-fakta tersebut secara logis; c. Mernjamin bahwa rancangan Peraturan Daerah lahir dari proses pengambilan keputusan yang berdasarkan logika dan fakta. Pada dasarnya, naskah akademik bukan merupakan keharusan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, akan tetapi sebuah naskah akademik sangat dibutuhkan dalam pembentukan atau penyusunan naskah akademik. Urgensi dari sebuah naskah akademik dalam proses pembentukan atau penyusunan sebuah naskah akademik antara lain: a. b. c. 131 Naskah akademik merupakan media nyata bagi peran serta masyarakat dalam proses pembentukan atau penyusunan peraturan perundang-undangan bahkan inisiatif penyusunan atau pembentukan naskah akademik dapat berasal dari masyarakat; Naskah akademik akan memaparkan alasan-alasan, fakta-fakta atau latar belakang masalah atau urusan sehingga hal yang mendorong disusunnya suatu masalah atau urusan sehingga sangat penting dan mendesak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan adalah aspek ideologis, politis, budaya, sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Manfaatnya adalah dapat mengetahui secara pasti tentang mengapa perlu dibuatnya sebuah peraturan perundang-undangan dan apakah peraturan perundang-undangan tersebut memamng diperlukan oleh masyarakat; Naskah akademik menjelaskan tinjauan terhadap sebuah peraturan perundangundangan dari aspek filosofis (cita-cita hukum), aspek sosiologis (nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat), aspek yuridis (secara vertikal dan horizontal tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya) dan aspek politis (kebijaksanaan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan-kebijakan dan tata laksana pemerintahan). Kajian filosofis akan menguraikan mengenai landasan filsafat atau pandangan yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan suatu masalah ke dalam peraturan perundangundangan. Untuk kajian yuridis, merupakan kajian yang memberikan dasar hukum bagi dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan, baik secara yuridis formal maupun yuridis materiil, mengingat dalam bagian ini dikaji mengenai landasan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan lain untuk memberi kewenangan bagi suatu instansi membuat aturan tertentu dan dasar hukum untuk mengatur permasalahan (objek) yang akan diatur. Kajian sosiologis menjelaskan peraturan dianggap sebagai suatu peraturan yang efektif apabila tidak melupakan bagaimana kebutuhan masyarakat, keinginan masyarakat, interaksi masyarakat terhadap peraturan tersebut. Sehingga dalam kajian ini realitas masyarakat yang meliputi kebutuhan hukum masyarakat, kondisi masyarakat dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang (rasa keadilan masyarakat 131.; Kajian politis pada prinsipnya mengedepankan persoalan kepentingan dari pihak terkait (pemerintah dan masyarakat) melalui kekuatan masing-masing pihak, oleh karena itu naskah akademik berperan menjadi sarana Mahendra Putra Kurnia dkk., op. cit., hal. 53 ... 232 memadukan kekuatan-kekuatan para pihak tersebut, sehingga diharapkan perpaduan tersebut menjadi sebuah kebijaksanaan politik yang kelak menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan-kebijakan dan pengarahan ketatalasanaan pemerintahan; d. Naskah Akademik memberikan gambaran mengenai substansi, materi dan ruang lingkup dari sebuah peraturan perundang-undangan yang akan dibuat. Dalam hal ini dijelaskan mengenai konsepsi, pendekatan dan asas-asas dari materi hukum yang perlu diatur, serta pemikiran-pemikiran normanya; e. Naskah Akademik memberikan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan bagi pihak eksekutif dan legislatif pembentukan peraturan perundangundangan tentang permasalahan yang akan dibahas dalam naskah akademik. Saat ini kecenderungan pandangan masyarakat yang menempatkan perundangundangan sebagai suatu produk yang berpihak pada kepentingan pemerintah (politik) semata sehingga dalam implementasinya masyarakat tidak terlalu merasa memiliki dan menjiwai perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu, Naskah Akademik diharapkan bisa digunakan sebagai instrumen penyaring, menjembatani dan upaya meminimalisir unsur-unsur kepentingan politik dari pihak pembentuk peraturan perundang-undangan, di mana Naskah Akademik yang proses pembuatannya dengan cara meneliti, menampung dan mengakomodasi secara ilmiah kebutuhan, serta harapan masyarakat, maka masyarakat merasa memiliki dan menjiwai perundang-undangan tersebut. Keberadaan naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sangat strategis dan merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan apabila membentuk peraturan perundang-undangan yang baik. Naskah akademik dapat dikatakan sebagai ”ruang public” yang memungkinkan aspirasi rakyat terakomodasi dalam penyusunan substansi peraturan perundang-undangan. Dengan naskah akademik, maka ruang-ruang publik (masyarakat) tersebut sangat terbuka dan masyarakat bebas mengeluarkan aspirasi serta melakukan apresiasi terhadap substansi peraturan perundang-undangan yang akan dan sedang diatur. Penutup Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan UndangUndang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pada tahap perencanaan naskah akademik haruslah selalu atau dengan kata lain pembuatan naskah akademik adalah mutlak, karena dalam naskah akademik tersebut dituangkan latar belakang dan tujuan penyusunan; ... sasaran yang ingin diwujudkan; dan 233 jangkauan dan arah pengaturan. Materi tersebut haruslah telah melalui pengkajian dan penyelarasan. Adapun yang dimaksud dengan “pengkajian dan penyelarasan” adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang vertikal atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan. DAFTAR PUSTAKA BUKU Maria Farida Indriati., S, 2007, Ilmu Perundang-Undangan 1, Penerbit Kanisius, Yogyakarta. Muchsan, 1981, Peradilan Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta. Maria Farida Indarti Suprapto, 1998, Ilmu Pembentukannnya, Kanisius, Yogyakarta. Perundang-undangan, Dasar-dasar Kansil, CST., Christine ST. Kansil, 2007, Memahami Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004), PT. Pradnya Paramita, Jakarta. Mahendra Putra Kurnia, Purwanto, Emilda Kuspraningrum, Ivan Zairani Lisi, 2007, Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisiptif (Urgensi, Strategi, dan Proses bagi Pembentukan Perda yang Baik), Kreasi Total Media (KTM), Yogyakarta. MAKALAH Aan Eko Widiarto, ”Metode dan Tekhnik Penyusunan Naskah Akademik”, Dosen Legal Drafting Universitas Brawijaya. Abdul Wahid, ”Penyusunan Naskah Akademik”, artikel perundang-undangan. Maria Farida Indrati, “Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia”, artikel peraturan perundang-undangan, Muhammad Waliyadin, “Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Perspektif Pemerintah”, artikel peraturan perundang-undangan. Qomaruddin, ”Dasar-Dasar Konstitusional Peraturan perundang-undangan”, artikel peraturan perundang-undangan. Wicipto Setiadi, “Pemantapan Pengelolaan Proses Perumusan Kebijakan Publik dan peraturan Perundang-undangan”, artikel peraturan perundang-undangan, www.legalitas.org SUMBER HUKUM UU No 12 tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Perpres 7 Tahun 2005 tentang RPJM 2004-2009, Direktorat Jenderal Perlindungan HAM, Departemen Kehakiman dan HAM, 2004. ... 234 TANGGUNG JAWAB PERBANKAN DALAM TRANSAKSI INTERNET BANKING I Gusti Ayu Suarniati Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar ayusuarniati [email protected] Abstract: Internet banking is a banking service that allows customers to obtain information, communicate and perform banking transactions via the Internet. Internet banking service provided is very practical, can directly conduct a transaction, global coverage, with no limit of time and place. Development of information technology will facilitate the one hand man in carrying out its activities, on the other hand is very risky at all of the actions that could harm the parties to a transaction, especially the customer. Bank as a business corporation in the event of a loss of customers in transactions with the internet banking system will be responsible to provide compensation if the error made by the bank. Key words: responsibilities of bank, bank, Internet banking transaction. Pendahuluan Menurut ketentuan Bank Indonesia , internet banking adalah salah satu pelayanan jasa bank yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan melakukan transaksi perbankan melaui jaringan internet. Ada dua tujuan yang ingin dicapai oleh suatu bank ketika ia memperluas layanan jasanya melalui internet banking. Tujuan tersebut adalah pertama, produk-produk yang komplek dari bank dapat ditawarkan dalam kualitas yang ekuivalen dengan biaya yang murah dan potensi nasabah yang lebih besar, kedua, dapat melakukan hubungan disetiap tempat dan kapan saja, baik pada waktu siang maupun malam. Dalam praktek pelaksanaan internet banking saat ini di Indonesia dan sesuai dengan PBI: 9/15/PBI/2007 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum dapat dilakukan dengan dua model yaitu: in house internet banking dan outsourcing internet banking. In house internet banking merupakan layanan internet banking oleh bank itu sendiri tanpa melibatkan pihak lain. Sedangkan outsourcing internet banking adalah bank dalam menerapkan layanan internet banking menggunakan jasa pihak lain. Dari segi ekonomi kemunculan tehnologi internet telah meningkatkan efisiensi biaya sekaligus memberikan keuntungan yang tinggi bagi sektor perbankan dan kemungkinan untuk memperluas pangsa pasar ke seluruh dunia, tetapi dilihat dari segi hukum masalahnya ... 235 akan menjadi lain, karena sampai saat ini instrumen hukum yang akan memberikan perlindungan baik kepada nasabah maupun bank itu sendiri masih kurang memadai. 132. Terlepas dari nilai lebih layanan internet banking, dari sudut pandang hukum kehadiran layanan internet banking masih menyimpan sejumlah permasalahan. Kondisi ini diperburuk lagi tatkala perubahan pada layanan internet banking baik dari segi teknologi maupun bisnis sangat cepat. 133 Permasalahan teknologi yang menyangkut pelaksanaan internet banking, yaitu adanya celah, human error, atau apapun yang bisa membuat suatu sistem memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut menyangkut aspek keamanan, dengan maraknya pemberitaan pembobolan. terhadap rekening miliknya nasabah melalui peralihan transfer, penyalah gunaan kartu kredit atau cara-cara lainnya. Perkembangan teknologi informasi disatu sisi akan mempermudah manusia dalam menjalankan aktivitasnya, di sisi lain dapat menimbulkan berbagai masalah yang memerlukan penanganan yang serius, seperti munculnya berbagai bentuk kejahatan baru yang dikenal dengan cyber crime. 134 Cyber crime merupakan suatu sisi gelap dari kemanjuan tehnologi yang mepunyai dampak yang luas dalam kehidupan modern. Suatu contoh kasus klik.bca.com, bagaimana kecanggihan teknologi informasi masih tetap dapat dirusak/ dimasukkan secara illegal, sehingga akibat dari ulah seorang hacker 130 user ID dan PIN milik nasabah Bank Central Asia dapat diketahui. 135 Masih banyak kasus-kasus lain yang merugikan para nasabah. Dalam transaksi-transaksi dengan sistem internet banking sangat riskan sekali dari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan pihak-pihak yang melakukan transaksi. Untuk menjamin adanya keamanan dan kenyamanan dalam melakukan transaksi internet banking, harus ada kepastian siapa yang akan bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap nasabah. Pengertian Tanggung Jawab dan Perjanjian Antara Bank dengan Nasabah Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, kalau ada sesuatu hal boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. 136. Tanggung jawab merupakan 132 Budi Agus Riswandi, 2003, Hukum dan Internet di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, (selanjutnya disebut Budi Agus Riswandi I, hal. 75. 133 Budi Agus Riswandi, 2005, Aspek Hukum Internet Banking, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, (selanjutnya disebut Budi Agus Riswandi II), hal. 2. 134 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, PT Refika Aditama, Bandung, hal.122. 135 Ibid, hal. 134. 136 Poerwadarminta, W.JS., 2003, Kamus Umum Bahasa Indonesia, disusun kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasiona., hal. 1205. ... 236 hasil yang ditimbulkan dari suatu perbuatan. Tanggung jawab dituntut karena ada suatu kesalahan yang dapat merugikan hak dan kepentingan orang lain. Dalam hukum, setiap tuntutan pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan seseorang harus (wajib) bertanggung jawab. Menurut Celina Tri Siwi Kristiyanti, prinsipprinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. Kesalahan (liability based on fault); Praduga selalu bertanggung jawab (presumption of liability); Praduga selalu tidak bertanggung jawab (presumption of nonliability); Tanggung jawab mutlak (strict liability); Pembatasan tanggung jawab (limitation of liability). 137 1. Prinsip Tanggung Jawab berdasarkan unsur kesalahan Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (fault liability atau liability based on fault) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUH Perdata, sebagai Pasal tentang perbuatan melawan hukum, yang mengharuskan dipenuhinya empat unsur pokok , yaitu: adanya perbuatan. adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita dan adanya hububngan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Secara common sense, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adalah adil bagi orang yang berbuat salah untuk menggantikan kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain. 138 2. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (presumption of liability principle), sampai dapat dibuktikan ia tidak bersalah jadi beban pembuktian ada pada si tergugat. 3. Prinsip Praduga untuk tidak Selalu Bertanggung Jawab Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab (presumption nonliability principle) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian secara common sense dapat dibenarkan. 4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (absolute liability) . Ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada pendapat yang mengatakan, strict liability, adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan force majeur. Sebaliknya, 137 Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 138 Ibid., hal. 93. 92. ... 237 absolute liability adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. 5. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability principle) , prinsip ini oleh pelaku usaha biasanya dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Sebagaimana diketahui hubungan antara nasabah dengan pihak bank didasarkan atas suatu perjanjian (kontrak). Sehingga asas-asas hukum perdata khususnya asas-asas hukum perikatan merupakan bagian dari oprasional perbankan. Hal penting yang perlu kita ketahui dalam hukum perikakatan atau perjanjian adalah syarat-syarat sahnya suatu perjajian. Menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian atau perikatan harus memenuhi 4 syarat, yaitu: 1. 2. 3. 4. Kesepakatan yang bebas dari orang-orang yang mengikatkan diri , kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, kemauan tersebut harus dinyatakan baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; Suatu hal yang tertentu yang diperjanjikan; dan Suatu “sebab” (oorzaak) yang halal,artinya tidak terlarang. 139 Beberapa asas hukum perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: 1. 2. 3. 4. 5. Asas Kebebasan berkontrak, dapat dianalis dari ketentun Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas Konsensualisme dari suatu perjanjian Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam Pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak . Asas Pacta Sunt Servanda Bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai ikatan hukum layaknya undang-undang, para pihak harus melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati dalam perjanjian. Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Asas Itikad Baik (Goede Trouw) Asas etikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata berbunyi Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak dalam perjanjian harus melaksankan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas Kepatutan Asas kepatutan berkaitan dengan isi perjanjian, dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata. Menurut asas ini isi perjanjian ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat. 139 Subekti, 1975, Pokok-Pokok dari Hukum Perdata, PT Intermasa, Jakarta, hal. 112. ... 238 Tanggung Jawab Pihak Bank Terhadap Nasabah Dalam Transaksi Internet Banking Kehadiran layanan internet banking sebagai media alternatif dalam memberikan kemudahan-kemudahan bagi nasabah suatu bank sepertinya merupakan solusi yang cukup efektif. Namun demikian terlepas dari nilai lebih layanan internet banking disisi lain membuatnya juga semakin berisiko.Dengan kenyataan seperti itu faktor keamanan menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Bank Indonesia mengingatkan bahwa berbagai risiko terkait pelayanan transaksi elektronik tetap menjadi tanggung jawab bank yang bersangkutan meski penyediaan jasa tersebut dilakukan oleh pihak lain. Menurut Internet Banking Comptroller’s Handbook (Comptroller of the Currency Administrator of National Banks) ditemukan beberapa katagori risiko yang ada dalam penyelenggaraan layanan internet banking, yaitu sebagai berikut: 140 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Credit Risk (risiko kredit), adalah risiko terhadap pendapatan atau modal yang timbul dari kegagalan obligator untuk menyepakati setiap kontrak dengan bank atau sebaliknya untuk performan yang disetujui. Interest Rate Risk (risiko suku bunga), adalah risiko terhadap pendapatan atau modal yang timbul dari pergerakan dalam suku bunga. Evaluasi dari suku bunga harus mempertimbangkan dampak yang komplek dari produk dan juga dampak potensial yang mengubah suku bunga pada fee. Liguidity Risk (risiko likuiditas), adalah risiko yang dihadapi oleh bank dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Layana intenet banking dapat meningkatkan volatility deposito dari nasbah yang semata-mata memelihara rekening pada the basis of rate. Aset/ liabilitas dan sistem manajemen pinjaman portofolio seharusnya menyediakan penawaran produk melalui layanan internet banking. Ditingkatnya pengawasan likuiditas dan perubahan pada deposito dan pinjamnan mungkin menggantungkan jaminan pada volume dan kegiatan rekening internet alamiah. Price Risk (Risiko harga), adalah risiko untuk laba atau modal yang timbul dari perubahan nilai portofolio diperdagangkan instrument keuangan. Bank mungkin terkena risiko harga jika mereka membuat atau memperluas brokering deposito. Foreign Exchange Risk (Risiko Kurs Devisa Kebijakan), risiko valuta asing hadir ketika portofolio pinjaman atau kredit adalah dalam mata uang asing atau didanai oleh pinjaman ditempat lain. Transaction Risk (risiko transaksi), adalah risiko yang prospektif dan banyak berdampak pada pendapan dan modal. Hal ini merupakan akibat adanya praktik penipuan, kesalahan, ketidakmampuan untuk penyerahan produk dan jasa, dan memelihara posisi kompetitif dan penawaran jasa serta memperluas produk layanan internet banking. Compliance Risk (Risiko Komplain), adalah risiko yang berdampak terhadap pendapatan dan modal akibat adanya pelanggaran terhadap hukum, aturan, regulasi, praktek yang ditentukan, atau standar etika. 140 Internet Banking Comptroller’s Handbook, 1999, “Comptroller of the Currency Administrator of National Banks”, http://docs google.com/viewer, diakses tanggal 4 Agustus 2010, hal. 5-12. ... 8. 9. 239 Strategi Risk (Risiko strategi), risiko strategi timbul dari keputusan bisnis yang merugikan implementasi, tidak tepat keputusan, atau kurang responsif terhadap perubahan industri. Reputation Risk (risiko reputasi), adalah merupakan sebagian besar dari prospek risiko yang bedampak kepada pendapatan dan modal akibat adanya pendapatan negatif dari publik. Hal ini berdampak pada penetapan hubungan baru atau layanan atau kelanjutan layanan hubungan konvensional. Layanan Internet Banking menggunakan media internet sebagai media komunikasi, maka keamanan dari layanan Internet Banking bergantung kepada keamanan dari internet. Secara umum pengguna terhubung ke internet melalui layanan Internet Service Provider (ISP), baik dengan menggunakan modem, cable modem, wireless, maupun dengan menggunakan leased line. ISP ini kemudian terhubung ke Internet melaui network provider lainnya. Disisi layanan internet banking terjadi juga hal yang serupa. Server Internet Banking terhubung ke internet melaui ISP atau network provider lainnya. Di sisi pengguna computer milik pengguna dapat disusupi virus dan Trojan horse, sehingga data-data yang berada di computer pengguna (seperti Nomor PIN, nomor kartu kredit dan kunci rahasia lainnya) dapat disadap, diubah, dihapus dan dipalsukan. Jalur antara pengguna dan ISP dapat juga disadap. Disisi ISP, informasi dapat juga disadap dan dipalsukan apabila sistem keamanan ISP ternyata renta, mungkin saja seorang cracker memasang program penyadap (siffer) yang dapat menyadap atau mengambil informasi tentang pelanggan. 141 Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh territorial suatu negara. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi. Di samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensip, dan dapat dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian dampak yang yang diakibatkannya pun bisa demikian komplek dan rumit. Bank Indonsia sebagai bank sentral telah mengeluarkan aturan mengenai pelaksanaan internet banking yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/15/PBI/2007 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, maupun aturan-aturan perbankan lainnya walaupun secara khusus tidak mengatur tentang internet banking tetapi dapat diterapkan dalam pelaksanaan transaksi internet banking. Peraturan perbankan belum mengatur mengenai bentuk pertanggungjawaban pihak bank 141 Budi Rahardjo, “Aspek Teknologi dan http://www.indocisc.com, diakses tanggal 9 Juli 2011, hal.3. Keamanan Dalam Internet Banking”, ... 240 terhadap kerugian yang diderita oleh nasabah dalam transaksi internet banking. Sehingga sebagai dasar hukum pertanggung jawaban pihak bank terhadap nasabah dalam transaksi internet banking dapat diterapkan ketentuan-ketentuan dalam: 1. KUH Perdata terutama Pasal-pasal: 1236, 1239, 1245, dan Pasal 1365. 2. Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, terutama Pasal 19; 3. Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, terutama Pasal 15 dan Pasal 21. Bentuk-bentuk pertanggung jawaban sebagai mana diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut diatas akan diuraikan sebagai berikut: 1. Konsep Pertanggung jawaban menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Dasar pertanggung jawaban menurut hukum perdata adalah kesalahan dan risiko yang ada dalam setiap peristiwa hukum. 142 Secara teoritis pertanggung jawaban terkait dengan hubungan hukum yang timbul antara pihak yang menuntut pertanggung jawaban dengan pihak yang dituntut untuk bertanggung jawab. Oleh karena itu, berdasarkan jenis hubungan hukum atau peristiwa hukum yang ada, dapat dibedakan: a. Pertanggung jawaban atas dasar kesalahan, yang dapat lahir karena terjadinya wanprestasi, timbulnya perbuatan melawan hukum, dan tindakan yang kurang hati-hati; b. Pertanggung jawaban atas dasar risiko, yaitu tanggung jawab yang harus dipikul sebagai risiko yang harus diambil oleh seorang pengusaha atas kegiatan usahanya. 143 Dalam hukum perdata dasar pertanggung jawaban ada dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian, dikenal pertanggung jawaban atas dasar kesalahan (liability based on faul) dan pertanggung jawaban tanpa kesalahan (liability without fault) yang juga dikenal dengan tanggung jawab risiko (risk liability) atau tanggung jawab mutlak (strict liability). 144 Prinsip pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia telah bersalah melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Prinsip pertanggung jawaban atas dasar kesalahan dianut dalam penuntutan ganti rugi karena wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 142 Junus Sidabolak,2010, Bandung, hal. 101. 143 Ibid. hal 102. 144 Ibid, hal. 125. Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, ... 241 KUH Perdata dan seterusnya atau pertangung jawaban dalam perbuatan melawan hukum. Dalam keadaan wanprestasi, kesalahan tidak lagi dipersoalkan, sebab ada anggapan hukum bahwa kalau ada seorang debitur wanprestasi, dianggap telah bersalah (presumption of fault) dan oleh karena itu kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh kreditur yang menuntut ganti rugi. Sebaliknya debitur yang harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah, misalnya dengan mengemukakan adanya keadaan memaksa (Force majeure), sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1245 KUH Perdata. Secara garis besarnya ada dua kategori tuntutan ganti kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk, baik berupa kerugian materiil, fisik maupun jiwa, yaitu tuntutan ganti kerugi berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian yang berdasarkan perbuatan melawan hukum. 145 a. b. Apabila tuntutan ganti kerugian didasarkan pada wanprestasi, maka tergugat dengan penggugat terikat dengan suatu perjanjian, pihak ketiga (bukan sebagai pihak dalam perjanjian) yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti kerugian dengan alasan wanprestasi. Tuntutan berdasarkan perbuatan melanggar hukum, berbeda dengan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perikatan yang lahir dari perjanjian (karena terjadinya wanprestasi), tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara produsen dengan konsumen, sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan walaupun tidak ada hubungan perjanjian sebelumnya. 2. Konsep Pertanggung jawaban menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang No. 8 Tahun 1999). Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan mengarahkan pelaku usaha selalu beritikad baik dalam melakukan kegiatannya.Tanggung jawab sebagai produsen sekurangkurangnya mencakup 2 aspek, yaitu: 146 1. Bertanggung jawab untuk menciptakan iklim berusaha yang sehat, baik antara sesama pelaku usaha maupun antara pelaku usaha dengan masyarakat konsumen. 2. Bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat konsumen, baik sendiri-sendiri maupun keseluruhan dari kemungkinan timbulnya kerugian terhadap diri konsumen maupun harta bendanya. 145 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hal 127. 146 Junus Sidabolak, op. cit., hal.92-93. ... 242 Dengan demikian, dari segi pertanggung jawaban produsen dibebani dua jenis tanggung jawab, yaitu tanggung jawab publik dan tanggung jawab privat (perdata). Pertanggung jawaban privat (perdata) diatur dalam Pasal 19-Pasal 28. Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 tahun 1999), mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran , dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1), dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi: 1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan; 2. Tanggung jawab kerugian atas pencemaran; 3. Tanggung jawab kerugian atas kerugian konsumen. 147 Berdasarkan hal tersebut maka adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggung jawaban pelaku usaha. Ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen. Ketentuan tersebut tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan komsumen ( Pasal 19 ayat (5)). Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) dapat diterapkan pada pelaku usaha dibidang perbankan. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan Undang_Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) secara positif harus diselaraskan dengan ketentuan tentang transaksi elektronik yang tercantum dalam UU ITE, karena transaksi elektronik sering kali membawa persoalan spesifik , sehingga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam ruang siber kerap tidak terjangkau oleh hukum positif konvensional seperti UUPK. Merkipun demikian, transaksi 147 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, op.cit., hal. 126. ... 243 online memiliki implikasi hukum yang sama dengan transaksi secara offline. Oleh karena itu ketentuan, ketentuan-ketentuan UUPK yang relevan dengan transaksi elektronik harus dapat diterapkan terhadap upaya perlindungan konsumen yang melakukan transaksi online. 148 3.Konsep tanggung jawab menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang No. 11 Tahun 2008) Pertanggung jawaban pelaku usaha dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang ITE diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 21, Pasal-pasal tersebut memuat: Pasal 15, (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroprasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinyanya. (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik. Pasal 21, (1) Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau malaui Agen Elektronik (2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: a. Jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi; b. Jika dilakukan melaui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksaaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau c. Jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik. (3) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik. (4) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroprasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik. Dari ketentuan Pasal Pasal tersebut dapat diketahui pada prinsipnya, tanggung jawab akan dipikul oleh pihak yang melakukan kesalahan atau kelalaian ( fault liability atau liability based on fault) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata maupun pidana . 148 Iman Syahputra, 2010, Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik, PT Alumni, Bandung , hal. 190. ... 244 Penutup Bank dalam transaksi elektronik (internet banking) sebagai produsen penyedia jasa layanan akan bertanggung jawab terhadap nasabah pengguna layanan internet banking yang mengalami kerugian, apabila kesalahan dilakukan oleh pihak bank. Pertanggung jawaban pihak bank adalah pertanggung jawaban atas dasar kesalahan (liability based on faul) sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UndangUndang Perlindungan Konsumen (Undang_Undang 8 Tahun 1999), Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, maupun Peraturan Perbankan . Berdasarkan sistem hukum yang ada kedudukan konsumen sangat lemah dibandingkan produsen, salah satu usaha untuk melindungi dan meningkatkan kedudukan konsumen adalah dengan menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam hukum tentang tanggung jawab produsen. Pihak Bank dalam transaksi elektronik sebagai produsen penyedia jasa layanan sudah sewajarnya dibebani tanggung jawab mutlak (strict liability), mengingat risiko dalam transaksi internet banking sangat tinggi dan banyak jenisnya. Sehingga bank akan lebih hati-hati dalam mengeluarkan produk layanan internet banking. Namun dengan memberlakukan prinsip strict liability dalam hukum tentang product liability, terutama pihak bank bukan berarti tidak mendapatkan perlindungan. Pihak bank masih diberi kesempatan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab dalam hal-hal tertentu yang dinyatakan oleh undang-undang, antara lain dalam hal dapat dibuktikan adanya keadaan memaksa, kesalahan, atau kelalaian pihak nasabah. DAFTAR PUSTAKA BUKU Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta. Budi Agus Riswandi, 2003, Hukum Dan Internet Di Indonesia, UII Press, Yogyakarta. Budi Agus Riswandi, 2005, Aspek Hukum Internet Banking, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta. Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, PT Refika Aditama, Bandung. Iman Syahputra, 2010, Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik, PT Alumni, Bandung. Poerwadarminta, W.JS., 2003, Kamus Umum Bahasa Indonesia, disusun kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Subekti, 1975, Pokok-Pokok dari Hukum Perdata, PT Intremasa, Jakarta. ... 245 Junus Sidabolak,2010, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung. Iman Syahputra, 2010, Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik, PT Alumni, Bandung. INTERNET Budi Rahardjo, “Aspek Teknologi dan Keamanan Dalam http://www.indocisc.com, diakses tanggal 9 Juli 2011, hal.3. Internet Banking”, Internet Banking Comptroller’s Handbook, October 1999, “Comptroller of the Currency Administrator of National Banks”, http://docs google.com/viewer, diakses tanggal 4 Agustus 2010. SUMBER HUKUM Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), terjemahan R Subekti dan R Tjitrosudibio Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektonik Peraturan Bank Indonesia No. 9/15/PBI/2007 Tentang Penetapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum. ... 246 DAFTAR RIWAYAT HIDUP Anak Agung Pradnyaswari, S.H., M.H. Dilahirkan di Denpasar, 28 November 1986. Menyelesaikan pendidikan S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana pada tahun 2008 dan S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana pada tahun 2010. Pernah berkarier sebagai Staf Notaris pada Kantor Notaris I Gusti Ngurah Maha Buana, SH sejak Mei 2008 sampai dengan Mei 2009, Staf Notaris pada Kantor Notaris Agus Sudana, SH.MKn sejak Mei 2008 sampai dengan Januari 2010. Saat ini bekerja sebagai Staf Kontrak pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar. Dapat dihubungi melalui telepon : 081936280422 dan email: [email protected]. IGN Parikesit Widiatedja, S.H., M.Hum. Lahir di Denpasar pada 21 Maret 1981. Pendidikan sarjana dan pascasarjana masing-masing diselesaikan pada tahun 2003 dan 2006 di Universitas Brawijaya Malang. Saat ini menjadi dosen Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana. Buku-buku yang pernah ditulis diantaranya Bunga Rampai Pemikiran Hukum Kontemporer, Liberalisasi Jasa dan Masa Depan Pariwisata Kita dan lain-lain. Ni Putu Yogi Paramitha Dewi, S.H., M.H. Alumnus Magister Hukum Bisnis pada Universitas Udayana. Pernah magang di kantor advokat dan menjadi asisten peneliti. Saat ini bekerja di kantor Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Bali. Penulis juga aktif menulis pada blog pribadi yakni http://www.yogimitha.blogspot.com dan dihubungi pada email [email protected]. Agung Wardana, S.H., LLM Menyelesaikan studi Master of Laws (LLM) di School of Law, University of Nottingham, Inggris. Saat ini menjadi staf pengajar hukum internasional pada Fakultas Hukum, Undiknas University. Pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Daerah Bali serta Sekretaris Eksekutif Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM (PBHI) Bali. Pada 2010-2011 mendapatkan penghargaan sebagai Fellow pada Internastional Fellowship Program (IFP) dari Ford Foundation, sebuah lembaga non-profit internasional di bidang pendidikan internasional yang berkedudukan di New York, AS. Sebelumnya, pada 2007 juga mendapatkan beasiswa dari Netherlands Education Service Organisation (NESO) untuk mengikuti Course on Strategic Environmental Assessment and Environmental Impacts Assessment (SEA and EIA) di International Training Centre (ITC), University of Twente, Belanda. Selain mengajar, saat ini aktif sebagai penulis lepas di media massa, praktisi hukum (advokat) dan terlibat dalam penelitian-penelitian dalam topik hukum lingkungan, keadilan sosial, dan ekologi politik. Tulisan populernya dapat diakses pada www.agungwardana.com dan dapat dihubungi lewat email: [email protected] I Made Badra Saat ini sedang menyelesaikan pendidikan pascasarjana pada konsentrasi Hukum dan Masyarakat di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Udayana. Bekerja sebagai PNS di Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Aktif pula dalam penelitian yang berhubungan dengan hukum dan kebudayaan. Dapat dihubungi melalui telp: 081353611567 ... 247 I Wayan Wiasta, S.H., M.H. Dilahirkan di Gianyar, 1 Januari 1957. Beralamat di Jl. Jagaraga, No. 19 Celuk, Sukawati, Gianyar. Menamatkan pendidikan Strata 1 dan Strata 2 di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Saat ini bekerja sebagai dosen di Universitas Mahasaraswati Denpasar dan menjabat sebagai wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar. Dapat dihubungi melalui email: [email protected] Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H. Dilahirkan di Gianyar, 13 Mei 1976. Menyelesaikan Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, S2 di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana. Meraih gelar Doktor dari Universitas Brawijaya Malang dengan konsentrasi di Bidang Hukum Ketenagakerjaan. Saat ini bekerja sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar. Selain sebagai dosen penulis juga sebagai narasumber dalam berbagai seminar baik skala regional, nasional dan internasional. Tulisannya telah dimuat dalam media cetak, jurnal ilmiah. Pada saat ini penulis juga duduk dalam keanggotaan Angota majelis Pengawas Daerah Notaris, Dewan Pengupahan Provinsi Bali, dan sebagai Pembina dan penasehat dari Serikat Pekerja Mandiri Regional Bali dan Serikat Pekerja di Bali Hyatt, Grand Hyatt Bali, Nusa Dua Beach Hotel, The Royal Beach Seminyak, Mercure Sanur Bali, dll. Penulis dapat dihubungi melalui email: [email protected] I Nyoman Edi Irawan SPd., S.H. Mendapatkan gelar sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar. Selain itu juga mendapatkan gelar sarjana pendidikan. Sehari-hari aktif sebagai advokat dan legal consultant pada Prasada Bali Law Office. Penulis juga mengabdikan ilmunya pada dosen di beberapa PTS di Denpasar dan sebagai tenaga pengajar bahasa Inggris. Penulis dapat dihubungi melalui [email protected]. Tjok Istri Sri Harwathy, S.H., M.M. Dilahirkan di Bima, 11 September 1957. Menamatkan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Udayana pada tahun 1984 dan pendidikan S2 Magister Manajemen tahun 2002 di IMNI Jakarta. Saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar. Aktif dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Dapat dihubungi melalui 08123806751. Made Emy Andayani Citra, S.H., M.H. Dilahirkan di Singaraja, 28 Agustus 1964. Menamatkan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar dan S2 pada Program Magister Hukum Universitas Udayana konsentrasi Hukum Bisnis. Saat ini bekerja sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar dan menjabat sebagai Wakil Dekan II. Aktif pada bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Pernah mendapatkan penghargaan sebagai dosen berprestasi baik di lingkungan civitas akademika maupun di tingkat Kopertis Wilayah VIII. Dapat dihubungi melalui 08123829184. Ni Luh Gede Yogi Arthani, S.H., M.H. Dilahirkan di Denpasar, 22 Desember 1980. Menamatkan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Udayana dan S2 pada Program Magister Hukum Universitas Udayana. Saat ini bekerja sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar. Aktif dalam bidang pengabdian masyarakat. Dapat dihubungi melalui 087862712727 atau [email protected]. ... 248 Dewi Bunga, S.H., M.H. Dilahirkan di Denpasar, 8 Februari 1987. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Udayana dan S2 di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana dengan predikat cumlaude. Saat ini bekerja sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar. Aktif pula sebagai narasumber hukum di pelbagai acara seminar, TV dan Radio. Berbagai tulisannya telah dimuat dalam media cetak, jurnal ilmiah serta diseminarkan baik dalam skala regional, nasional dan internasional. Dapat dihubungi melalui [email protected] atau 081916151963. Agung Dwi Astika, S.H., M.H. Dilahirkan Denpasar, 15 Agustus 1973. Aktif dalam kegiatan diantaranya menjadi anggota Senat, Ketua UKM MBU Udayana, Ketua Karang Taruna Kecamatan, Pengurus Karang Taruna Kodya, dan Provinsi, Pengurus Peradi Bali dan Pengurus IKADIN kota Denpasar. Menjadi advokat sejak 1998. Pernah menjadi Direktur LBH Bali 2006 sd 2009. Penulis juga menjadi Trainer bagi paralegal di Bali dan Tim penyuluh KDRT Bali. I Gusti Ayu Suarniati, SH.,M.H. Dilahirkan di Bangli pada tanggal 19 Agustus1955. Menamatkan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Univ. Udayana dan pendidikan S2 pada Program Magister Ilmu Hukum Univ. Udayana konsentrasi Hukum Bisnis. Saat ini bekerja sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, aktif dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Dapat dihubungi melalui 08164727316 ... 249 KETENTUAN UMUM PENULISAN JURNAL ADVOKASI HUKUM Jurnal Advokasi Hukum merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar. Sebagaimana tulisan ilmiah, maka terdapat ketentuan-ketentuan terkait dengan penulisan pada jurnal ini. Adapun ketentuan-ketentuan yang dimaksud adalah: 1. Tulisan yang diterima adalah menyangkut masalah advokasi baik dalam kajian pidana, perdata, tata negara dan tata usaha negara, maupun kajian bisnis. 2. Tulisan belum pernah dimuat atau tidak sedang diajukan pada jurnal atau penerbit lain. 3. Judul ditulis dengan huruf kapital dan maksimal terdiri atas 12 kata. 4. Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris maksimal 200 kata dan memuat kata kunci 3-5 kata. 5. Naskah diketik di atas kertas HVS A4, 2 spasi, margin atas dan kiri 4 cm dan margin kanan dan bawah 3 cm dengan jumlah halaman antara 14-20 halaman. 6. Pada bagian akhir tulisan disertai dengan daftar riwayat hidup singkat yang sekurang-kurangnya melampirkan nama, tempat dan tanggal lahir, riwayat pendidikan, afiliasi serta alamat kontak yang dapat dihubungi (alamat/ email/ HP/ blog). 7. Penulisan catatan kaki adalah sebagai berikut: Buku: nama pengarang, tahun terbit, judul buku (cetak miring), penerbit, kota, halaman. contoh: Abdul Ghofur Anshori, 2009, Filfasat Hukum, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 25. Makalah: Nama pengarang, judul makalah (dalam tanda kutip), tema seminar/ lokakarya, penyelenggara, tempat, waktu, halaman. Contoh: Muladi, “Fungsionalisasi Hukum Pidana di Dalam kejahatan yang Dilakukan oleh Korporasi”, Makalah pada seminar nasional kejahatan korporasi, FH UNDIP, Semarang, 23-24 November 1989, hal. 2. Internet: Nama pengarang, edisi, judul (dalam tanda kutip), alamat web, tanggal akses. Agus Raharjo, 2006, “Kebijakan Kriminalisasi dan Penanganan Cybercrime di Indonesia”, http://www.unsoed.ac.id/newcmsfak/UserFiles/File/HUKUM/kriminalisasi_cybercrime.htm, diakses pada 9 Juni 2011. Jurnal: Nama penulis, judul (dicetak miring), nama jurnal, penerbit, edisi, halaman. Tjok Istri Sri Harwathy, Pengaruh Kebudayaan Terhadap Penegakan Hukum di Masyarakat, Maha Yustika, Fakultas Hukum Mahasaraswati Denpasar, Vol. 7 No. 7 September 2010, hal. 5. 8. Penulisan daftar pustaka adalah sebagai berikut: Buku: nama pengarang, tahun terbit, judul buku (cetak miring), penerbit, kota. contoh: Abdul Ghofur Anshori, 2009, Filfasat Hukum, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. ... 250 Makalah: Nama pengarang, judul makalah (dalam tanda kutip), tema seminar/ lokakarya, penyelenggara, tempat, waktu. Contoh: Muladi, “Fungsionalisasi Hukum Pidana di Dalam kejahatan yang Dilakukan oleh Korporasi”, Makalah pada seminar nasional kejahatan korporasi, FH UNDIP, Semarang, 23-24 November 1989. Internet: Nama pengarang, edisi, judul (dalam tanda kutip), alamat web, tanggal akses. Agus Raharjo, 2006, “Kebijakan Kriminalisasi dan Penanganan Cybercrime di Indonesia”, http://www.unsoed.ac.id/newcmsfak/UserFiles/File/HUKUM/kriminalisasi_cybercrime.htm, diakses pada 9 Juni 2011. Jurnal: Nama penulis, judul (dicetak miring), nama jurnal, penerbit, edisi. Tjok Istri Sri Harwathy, Pengaruh Kebudayaan Terhadap Penegakan Hukum di Masyarakat, Maha Yustika, Fakultas Hukum Mahasaraswati Denpasar, Vol. 7 No. 7 September 2010. Sumber Hukum: Nama sumber hukum, lembaran negara dan lembaran tambahan negara. contoh: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843. 9. Pengiriman naskah dilakukan dengan menyertakan hard copy dan soft copy yang dikirim ke alamat redaksi “Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Jalan Kamboja, Denpasar”, contact person: Ni Luh Yogi Arthani,SH,MH (087862712727/ [email protected]). 10. Naskah yang diterima oleh redaksi akan di review dan apabila diterbitkan maka redaksi akan menghubungi penulis. 11. Redaksi berhak atas naskah yang dikirimkan oleh penulis. Salam Redaksi