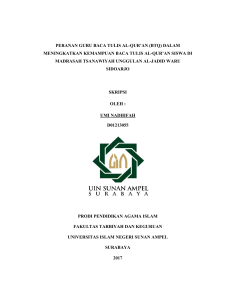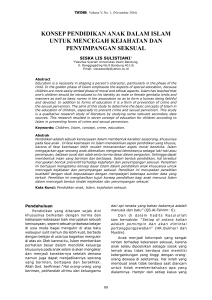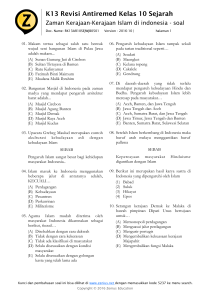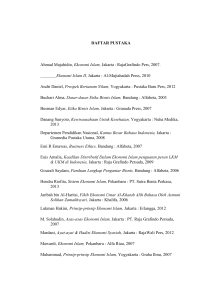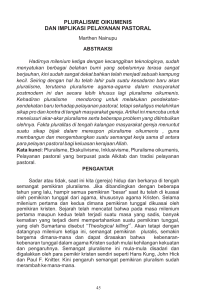bab ii tinjauan pustaka
advertisement

15 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu Hasil penelitian M. Lutfi Mustofa (2010) tentang etika pluralisme di kalangan warga nahdliyin di Jawa Timur menyebutkan bahwa; (1) konsepsi NU mengenai pluralisme keagamaan terkonstruksi dan tumbuh berkembang dalam konteks sejarah dan sosialnya melalui proses dialektika teologis, ideologis, dan sosio-kultural; (2) keterlibatan NU dalam mempromosikan dan memelihara nilainilai pluralisme keagamaan di Jawa Timur menampakkan gambaran yang beraneka ragam, dari yang bersifat responsif, kontra produktif, dan pada elemen terbesarnya bersikap diam (silent majority); (3) dampak psiko-sosial etika pluralisme NU terhadap relasi-relasi internal maupun eksternal NU di Jawa Timur, paling tidak dapat dirasakan dan disaksikan dari semakin menguatnya kontestasi antara kelompok konservatif dan progresif. Pro-kontra pluralisme keagamaan di dalam NU Jawa Timur, sekalipun tidak sepanas di dunia politik, tetapi setidaknya hal ini telah menimbulkan keprihatinan pada kelompokkelompok minoritas dan marjinal akan ancaman melemahnya kekuatan civil society yang selama ini telah dicontohkan oleh Gus Dur dan NU. Ada tiga aspek yang menjadi fokus penelitian Mustofa, yaitu: (1) pertama, konsepsi pluralisme keagamaan NU yang terelaborasi dalam konstitusi organisasi maupun pemikiran komunitas nahdliyin; (2) bentuk-bentuk keterlibatan aktif NU dalam mempromosikan dan memelihara nilai-nilai pluralisme keagamaan; (3) dampak psiko-sosial etika pluralisme keagamaan NU dalam relasi-relasi internal maupun eksternal komunitas nahdliyin. Gagasan dan praktik pluralisme keagamaan di dalam NU memiliki akarakar ideologis dan teologis sangat jauh ke belakang, yang berakar pada perkembangan pemikiran dan praktik keagamaan dalam sejarah masyarakat muslim hingga pada masa-masa kenabian. Menurut Mustofa, dalam persoalan pluralisme keagamaan tersebut bukan hanya berkaitan dengan akar-akar ideologis dan teologis, tetapi telah berkembang menjadi salah satu elemen utama dari wacana civil society yang berkaitan dengan posisi dan agenda politik NU pada 16 paroh terakhir 1990-an. Sebagai organisasi sosial-keagamaan, kiprah NU tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan norma-norma keislaman yang secara baku disusun dalam konstitusi fiqh maupun teologinya, termasuk untuk mempromosikan gagasan dan praktik pluralisme keagamaan. Meminjam istilah Berger (1966), nilai-nilai dan norma-norma keislaman inilah yang dalam waktu sangat lama merupakan faktor penting yang ikut membentuk realitas sosial komunitas NU di Indonesia. Hasil penelitian Umar dan Priyangga (2007) tentang pluralisme agama dan paham keagamaan di Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa pluralisme agama dan paham keagamaan tidak menjadi kendala dalam menciptakan toleransi kehidupan beragama baik antar umat beragama maupun intern umat beragama. Menurut Umar dan Priyangga, hampir tidak pernah terjadi keributan dan konflik akibat perbedaan agama dan paham keagamaan. Dalam penelitiannya, Umar dan Priyangga menyimpulkan bahwa kerukunan yang terjadi di kota Bandar Lampung, baik antar umat beragama dan intern umat beragama (Islam) tidak terlepas dari peran Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung, tokoh agama serta pemimpin Ormas Islam yang senantiasa membina umat dalam bentuk dialog antar umat beragama dan dialog antar pemerintah dengan umat beragama. Forum Aksi Sosial dan Kerjasama Antar Umat Beragama Lampung (FASKAUBAL) yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk menangani kerukunan antar umat beragama berperan besar dalam menciptakan pluralisme keberagamaan dan hidup toleransi di Kota Bandar Lampung. Kajian Syafru El Fauzi (2007) tentang Jemaat Ahmadiyah menunjukkan bahwa kelompok keagamaan yang berkembang di Indonesia sejak tahun 1925 hingga kini tidak pernah aman dari kritikan dan kecaman. Hal itu terlihat dari respon beberapa ormas Islam terhadap Jemaat Ahmadiyah, seperti Muhammadiyah, NU dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Respon negatif dari ormas-ormas Islam ini lebih bersifat teologis ketimbang sosiologis. Sementara itu, kajian Iskandar Zulkarnain (2006) lebih menitikberatkan pada gerakan organisasi Jemaat Ahmadiyah antara tahun 1920-1942. Dari sudut pandang yang lain, Zaenuri (2009) meneliti konflik Jemaat Ahmadiyah dengan masyarakat non Ahmadiyah. Dalam penelitiannya ditemukan 17 bahwa konflik yang terjadi antara Jemaat Ahmadiyah dan masyarakt non Ahmadiyah di Lombok lebih disebabkan karena proses komunikasi yang tidak efektif (komunikator, pesan dan metode), baik dari kalangan Jemaat Ahmadiyah maupun dari masyarakat Lombok. Penelitian yang terkait dengan pluralisme dan Jemaat Ahmadiyah ditulis oleh Budiwanti (2009). Dalam tulisannya, Budiwanti mengatakan bahwa pluralisme di Indonesia sudah runtuh melihat perlakuan masyarakat, ormas Islam dan MUI kepada Jemaat Ahmadiyah. Menurut Budiwanti fatwa MUI tentang Jemaat Ahmadiyah yang sesat menjadi legitimasi bagi organisasi Islam radikal untuk menyerang Jemaat Ahmadiyah. 2.2. Pluralisme Keberagamaan Pluralism adalah istilah kefilsafatan yang diadopsi dari Bahasa Inggris, plural yang berarti jamak atau banyak dengan implikasi perbedaan, dan ism yang berarti paham atau aliran. Dengan demikian, istilah pluralisme selengkapnya dapat diartikan sebagai paham atau aliran kefilsafatan yang mengakui secara sungguhsungguh terhadap kenyataan bahwa terdapat banyak kelompok manusia yang berbeda-beda dalam suatu negara, baik atas dasar etnis, ras, budaya, agama dan kepercayaan. Menurut The Oxford English Dictionary, seperti yang dikutip Abdillah (2001) disebutkan, bahwa pluralisme dipahami sebagai: (1) suatu teori yang menentang kekuasaan negara monolitis, dan mendukung desentralisasi dan otonomi untuk organisasi-organisasi utama yang mewakili keterlibatan individu dalam masyarakat. Suatu keyakinan bahwa kekuasaan itu harus dibagi bersamasama di antara sejumlah partai politik. (2) keberadaan atau toleransi keragaman etnik atau kelompok-kelompok kultural dalam suatu masyarakat atau negara, serta keragaman kepercayaan atau sikap dalam suatu badan, kelembagaan, dan sebagainya. Definisi yang pertama mengandung pengertian pluralisme politik, sedangkan definisi kedua mengandung pengertian pluralisme sosial atau primordial. Namun demikian, sebagaimana perhatian utama tesis ini adalah mengenai agama dan interaksi antarkelompok keagamaan, maka istilah pluralisme akan digunakan dalam konteks agama. Pluralisme keberagamaan di sini diartikan 18 sebagai gagasan atau paham yang mengandaikan: (1) kelompok keagamaan yang berbeda-beda dapat berkoeksistensi di dalam satu masyarakat di bawah sistem teologi dan hukum mereka sendiri, dan (2) tidak satu kelompok pun yang dapat memonopoli terhadap keselamatan. Pluralisme di sini juga dibedakan dari inklusivisme, karena keduanya memiliki kerangka paradigmatiknya sendiri dalam melihat agama. Apabila inklusivisme meniscayakan pemahaman terhadap agama lain dari segi adanya dimensi kesamaan substansi dan nilai, maka pluralisme justru mengakui dan menegaskan adanya perbedaan-perbedaan. Pluralisme tidak saja dibedakan dari inklusivisme, tetapi juga dibedakan dari subyektivisme, relativisme, multikulturalisme, dan globalisme (Boase 2005, Rahman 2001). Dengan kata lain, pluralisme hendak membangun pemahaman mengenai agama-agama itu sebagaimana realitas mereka sendiri yang memang berbedabeda. Hanya saja, dalam memberikan respons terhadap diversitas tersebut pluralisme menawarkan sesuatu yang baru. Pertama, ia menghendaki keterlibatan aktif setiap individu untuk menyulam perbedaan-perbedaan tersebut, guna mencapai tujuan kebersamaan. Kedua, ia tidak sekadar menganjurkan penghargaan terhadap yang lain (toleransi), tetapi lebih pada ikhtiar membangun pemahaman yang konstruktif (constructive understanding) mengenai orang lain (religious others). Ketiga, ia bermaksud menemukan komitmen bersama di antara keanekaragaman komitmen (encounter commitments). Jadi, sangat berbeda dengan relativisme, karena apabila pluralisme hendak mencapai komitmen bersama untuk kemanusiaan, maka relativisme justru menegasikannya, bahkan mengingkari kebenaran agama-agama itu sendiri (Misrawi 2007). Shihab (1999) juga mengisyaratkan bahwa dalam pluralisme yang terpenting adalah bukan semata-mata berupa pengertian yang merujuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan, namun juga keterlibatan aktif dalam kemajemukan tersebut. Partisipasi tersebut ditunjukkan melalui sikap interaktif secara positif dalam lingkungan yang majemuk, tidak melakukan klaim dan monopoli atas suatu kebenaran, serta bersikap terbuka terhadap perbedaanperbedaan yang ada. 19 Diana L. Eck berpendapat, seperti yang ditulis Omid Safi (2003), Misrawi (2007) dan Ali (2003) bahwa terdapat tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam pluralisme, yaitu: 1) pluralisme sama sekali tidak sama dengan perbedaan (diversity), seperti masyarakat yang berlatar belakang agama dan etnik yang berbeda. Perbedaan latar belakang ini membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lain; 2) tujuan pluralisme sama sekali bukan bersikap ”toleransi” terhadap orang lain tetapi lebih dari itu ada upaya aktif untuk mencapai pemahaman satu sama lain; 3) pluralisme berbeda dengan relativisme. Jika pluralisme hendak mencapai komitmen bersama untuk kemanusiaan, maka relativisme justru menegasikan dan mengingkari kebenaran agama-agama itu sendiri. Pluralisme keberagamaan (Banchoff 2008) merupakan konsep yang melampui konteks nasional dan politik. Dalam teologi, terma pluralisme keberagamaan kerapkali menganjurkan sikap-sikap harmoni, tindakan terlibat di satu tempat, atau kesesuaian dengan orang lain yang melampaui tradisi-tradisi keberagamaan sebagai lawan dari sikap eksklusivisme keagamaan. Dalam sosiologi, pluralisme keberagamaan mengacu kepada tradisi-tradisi keberagamaan yang berbeda-beda di dalam ruang sosial atau kultural yang sama. Pluralisme keberagamaan juga mengacu pada pola-pola interaksi damai diantara aktor-aktor pemeluk agama yang berbeda-beda, yaitu individu dan kelompok yang bertindak menurut cara-cara keagamaan tertentu. Berdasarkan atas berbagai kajian terhadap gagasan dan praktek pluralisme keberagamaan di berbagai kawasan, para sarjana telah menyusun beragam pengertian pluralisme keberagamaan yang berbeda-beda. Sebagian pengertian tersebut sekalipun pada intinya dimasudkan untuk memperjelas arti penting etika global ini dalam menciptakan harmoni antarumat beragama, namun tidak semuanya digunakan sebagai definisi operasional dalam kajian ini. Konsep pluralisme dalam penelitian ini mengacu pada konsep Diana L. Eck (2006). 2.3. Fundamentalisme dan Konflik Keberagamaan Ketika Islam datang, sebenarnya kepuluan Nusantara sudah mempunyai peradaban yang bersumber dan pengaruh dari kebudayaan Hindu-Budha dari India, yang penyebaran pengaruhnya tidak merata. Para sejarawan sepakat bahwa penyebaran Islam di Indonesia dilakukan melalui proses dan pola secara damai 20 (Azra 1999; Hidayat 2012; Madjid 1998). Berbeda dengan penyebaran Islam di Timur Tengah yang dalam beberapa kasus disertai dengan pendudukan wilayah oleh militer Muslim. Islam dalam batasan tertentu disebarkan dengan pedang, kemudian dilanjutkan oleh para guru agama (da`i) dan pengembara sufi (Sunanto 2010). Islam masuk ke Indonesia (Nusantara) semula diperkenalkan oleh para pedagang Arab melalui jalur perdagangan di Samudera Hindia. Arus Islam ke Nusantara pada gilirannya juga melibatkan partisipasi pedagang-pedagang dari India (Gujarat), Persia dan China yang juga membawa pengaruh kebudayaan mereka masing-masing (Latif 2011). Para pedagang ini membawa Islam dengan cara damai sejalan dengan karakter pedagang itu sendiri yang bersahabat, terbuka dan menjalin relasi dengan orang lain. Sifat pedagang ini rupanya sejalan dengan semangat dakwah yang juga selalu ingin menawarkan dan menyebarkan ajaran Islam di wilayah baru. Menarik untuk diperhatikan bahwa Islam yang dikembangkan pada masamasa awal lebih banyak bermuatan tasawuf (esoterisme) yang berasal dari Persia dan India, sehingga ekspresi dan artikulasi Islam pada saat lebih inklusif, esoterik dan ramah (Hidayat 2012). Genealogi historis ini mungkin dapat menjelaskan mengapa Islam yang berkembang di Nusantara yang tadinya menjadi pusat Hindu-Budha berubah menjadi pusat Islam terbesar di dunia. Warisan berbagai candi yang tersebar di Indonesia telah cukup menjadi bukti betapa Indonesia dulu menjadi pusat agama Hindu dan Budha, di samping agama dan kepercayaan lokal yang sebagiannya masih bertahan hingga sekarang. Genealogis historis-teologis masuknya Islam ke Indonesia ini telah memberi karakter ekspresi keislaman di Indonesia hingga saat ini. Corak keislaman yang berkembang di Indonesia lebih bersifat kultural yang sangat apresiatif dan akomodatif terhadap tradisi lokal tanpa kehilangan substansi dari ajaran Islam itu sendiri. Karena itu (Madjid 1998), perkembangan kebudayaan Islam di Indonesia sebagian besarnya merupakan hasil dialog antara nilai-nilai Islam yang universal dan nilai-nilai kultural kepulauan Nusantara. Kendati demikian, keberagamaan umat Islam di negara ini bukan berarti seutuhnya berwajah mulus. Dalam periode dan di daerah tertentu, sikap 21 fundamentalisme dari kelompok Islam tertentu ikut menghiasi wajah keislaman Indonesia. Menurut Abd A`la (2008), peristiwa awal yang melakukan fundamentalisme keberagamaan adalah ketika meletusnya gerakan Padri yang bukan saja kepada orang di luar Islam, tapi kekerasan juga dilakukan kepada sesama muslim yang tidak mau mengikuti ajaran mereka. Kekerasan dan tindakan sejenis dapat dirujuk pandangan keagamaan tertentu yang sampai derajat tertentu melegitimasi atas terjadinya sikap dan tindakan semacam itu. Menurut Azra (1996) dan A`la (2008), sikap fundamentalisme keagamaan tersebut dapat dilacak dan dipengaruhi oleh pandangan aliran keagamaan Wahabi di Arab Saudi. Menurut Benda (1958 dalam A`la, 2008), gerakan Wahabi yang lahir di Arab Saudi itu telah memberikan tarikan magnetik kepada muslim Indonesia melampaui perbedaan doktrinal yang ada. Kaum Wahabi adalah kelompok keagamaan yang sangat tidak toleran dengan praktek-praktek yang bersifat bid`ah, khurafat dan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Siapa saja yang menyimpang, kelompok Wahabi siap ”meluruskan,” atau jika perlu diperangai dengan jalan kekerasan. Mereka berusaha melakukan purifikasi keagamaan sesuai dengan prinsip yang mereka anut dan akan meluruskan ritual keagamaan yang dianggap tidak sesuai melalui cara mereka sendiri. Dalam hal ini, ajaran mereka yang rigid tersebut, tidak bisa dilepaskan dari pemahaman keagamaan mereka yang literalskriptualistik. Gerakan Islam fundamentalisme di Indonesia memiliki genealogi dengan gerakan Islam salafi yang berkembang di Timur Tengah, khususnya Arab Saudi. Entah suatu kebetulan atau memang seperti itu, kebanyakan tokoh-tokoh gerakan Islam radikal di Indonesia adalah keturunan Arab, seperti Habieb Riziq Syihab, pemimpin Front Pembela Islam (FPI), Ja’far Umar Thalib (Laskar Jihad), Abu Bakar Ba’asyir (Majelis Mujahidin Indonesia), Habieb Husein al-Habsyi (Ikhwanul Muslimin), Hafidz Abdurahman (Hizbut Tahrir Indonesia). Terma fundamentalisme, jelas Karen Armstrong (2000), awalnya merujuk kepada sebutan yang dilekatkan kepada kelompok tertentu dari kalangan Protestan Amerika awal abad kedua puluh. Mereka menyebut diri mereka sebagai kelompok 22 fundamentalis untuk membedakan dari kaum Protestan liberal yang dalam anggapan mereka telah mengalami distorsi keimanan yang benar. Kaum fundamentalisme ini menekankan ajaran dan praktek pada tradisi dan prinsip Kristen melalui pemaknaan biblikal yang literalistik. Sebagai istilah yang diproduksi dalam tradisi Barat, maka istilah ini tidak cukup dikenal dalam tradisi Islam, meskipun gejala dan perilaku yang kurang lebih sama dapat kita temukan dalam tradisi dan sejarah muslim. Dalam Islam, fundamentalisme biasanya diterjemahkan dengan al-Ushuuliyyah al-Islaamiyyah (fundamentalisme Islam), al-Salaafiyah (warisan leluhur), al-Sahwah alislamiyyah (kebangkitan Islam), al-Ihyaa` al-Islami (kebangkitan kembali Islam). Namun, di kalangan intelektual berbeda-beda dalam menggunakannya, seperti ”ekstremisme Islam” oleh Gilles Kepel, ”Islam Radikal” oleh Emmanual Sivan (1990), dan yang lain ada yang menggunakan istilah ”integrisme,” revivalisme,” atau ”Islamisme” (Euben 2002). Sebutan-sebutan tersebut oleh kalangan tertentu juga sering disebut sebagai fenomena ”kebangkitan Islam” atau ”intensifikasi Islam” dalam wajah yang baru. 3 Bagi Azra (1996), karakteristik fundamentalisme adalah paham perlawanan terhadap modernitas, sekularisasi dan tata nilai barat, penolakan terhadap hermeneutika, penolakan terhadap pluralisme dan relativisme keberagamaan dan penolakan terhadap perkembangan historis dan sosiologis yang membuat mereka mudah terperangkap dalam tindakan kekerasan. Fundamentalisme Islam, lanjutnya, bisa dikatakan merupakan bentuk ekstrem dari gejala revivalisme. Habermas (dalam Borradori 2005) melihat bahwa salah satu karakteristik utama fundamentalisme terletak pada kekakuan sikap yang ditampakkan; mentalitas, sikap kepala batu yang menekankan pada pemaksaan secara politik keyakinan-keyakinan sepihak, terutama yang berkaitan dengan kepercayaan keagamaan, kendati hal tersebut tidak dapat diterima secara rasional. Sedikit berbeda dengan penjelasan di atas, Arkoun (1999), menjelaskan bahwa gerakan fundamentalisme Islam terbentuk secara menyeluruh dari oposisi, 3 Rumadi (2009) menjelaskan bahwa istilah-istilah tersebut digunakan untuk menunjuk gejala “kebangkitan Islam” yang diikuti dengan militansi dan fanatisme yang terkadang sangat ekstrim. Fundamentalisme lebih banyak berangkat dari literalisme dalam menafsirkan teks agama dan berakhir pada tindakan dengan wawasan sempit yang terkadang menindas dan menyalahkan kelompok lain. 23 tuntutan, susunan ideologis dan halusinasi individual yang tidak membawa kita kepada Islam sebagai agama atau warisan pemikiran, tetapi semata-mata kepada kemampuan setiap ideologinya dalam menggerakkan fantasi kolektif. Fundametalisme Islam yang berkembang di belahan dunia saat ini sama sekali bukanlah hal yang baru. Brown (2003) mencatat bahwa fundamentalisme merupakan fenomena global dan tidak saja terdapat di kalangan Islam saja melainkan juga di kalangan kaum Kristen, Yahudi, Hindu, Sikh dan Budha. Faktor-faktor, lanjutnya, yang melahirkan gerakan fundamentalisme bisa disebabkan oleh ekonomi, politik, militer dan sosial. Terlepas dari rumusan yang berbeda-beda, namun dapat ditarik benang merahnya bahwa fundamentalisme merupakan pola keberagamaan (bukan agama) untuk kembali kepada sumber ajaran secara rigid sebagai respon terhadap segala sesuatu yang dalam anggapan mereka merupakan krisis terhadap kepercayaan yang mereka yakini. Senada dengan ini, John O. Voll (dalam Euben, 2002) menjelaskan bahwa fundamentalisme dalam Islam, tepatnya dalam aliran Sunni, adalah sebagai penegasan kembali prinsip-prinsip mendasar dan usaha untuk membentuk ulang masyarakat berdasarkan dasar-dasar tadi ke dalam dunia politik dan sosial kontemporer. Munculnya gerakan-gerakan Islam fundamentalisme berkait erat dengan kegagalan negara menerapkan pola manajemen keragaman keagamaan (religious diversity) secara tepat. Dalam ruang sosial yang menghambat tumbuhnya kohesi sosial dan kesalingpercayaan antarkomponen masyarakat, fundamentalisme agama dapat tumbuh dengan mekar. Fundamentalisme agama itu sendiri merupakan cerminan dari lemahnya kohesi sosial. Dari sudut pandang sosiologis, gejala ini berhubungan dengan ekspansi modernisasi yang menciptakan kondisi dunia modern yang sangat paradoksal dan ini menimbulkan tekanan terhadap sistem disposisi berkelanjutan individual yang mengintegrasikan pengalaman-pengalaman masa lalu dan berfungsi sebagai matriks persepsi dan tindakan. Dalam kondisi-kondisi tertentu fundamentalisme agama tidak bisa dilepaskan dari sikap-sikap fanatisme dan eksklusifisme beragama yang pada 24 akhirnya melahirkan sikap intoleransi pada kelompok lain, bahkan menimbulkan konflik. Konflik muncul karena mereka yang memahami doktrin agama secara literal dan menolak kontekstual teks-teks agama tidak toleran dengan pemahaman dan penafsiran kelompok lain yang berbeda dengan mereka. Sikap eksklusifisme dalam penafsiran teks-teks agama serta menolak berbagai kemungkinan penafsiran lain berpengaruh pada terciptanya konflik dalam masyarakat. Hubungan antar umat beragama saat ini berada pada situasi yang cukup pelik. Gambaran ini jelas berbeda jauh jika dibandingkan dengan kondisi sebelum reformasi di mana hubungan antarumat beragama dianggap jauh lebih rukun dengan sedikit konflik. Berbagai peristiwa mutakhir terkait intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan atas nama agama dimungkinkan telah berkontribusi dalam membentuk persepsi publik dalam menilai situasi mutakhir kondisi hubungan antar umat beragama (Hasani et. al 2011). 2.4. Jemaat Ahmadiyah di Pedesaan Indonesia Ahmadiyah adalah suatu ajaran dan gerakan keagamaan yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) asal Qadian, Punjab, India. Dalam perkembangannya, Ahmadiyah terbagi ke dalam dua golongan, yaitu Ahmadiyah Lahore dan Ahmadiyah Qadian. Perbedaan kedua kelompok ini terletak pada keyakinan pada sosok Mirza Ghulam Ahmad. Ahmadiyah Qadian berpendapat bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi karena mereka mempercayai kenabian itu akan tetap ada sesudah Nabi Muhammad. Sementara itu, Ahmadiyah Lahore berpendapat bahwa Mirza Ghulam Ahmad bukanlah nabi melainkan seorang reformis agama (mujaddid) karena pintu kenabian setelah Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi. Ajaran dan gerakan keagamaan Ahmadiyah Lahore pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1924 di Yogyakarta dan kini menyebar ke berbagai daerah dan pedesaan di Indonesia. Ahmadiyah Lahore dibawa oleh dua orang muballigh Hindustan, yakni Maulana Ahmad dan Mirza Wali Ahmad Baig. Sementara itu, Ahmadiyah Qadian masuk ke Indonesia pada tahun 1925 melalui Aceh, Padang dan Pulau Jawa. Masuknya ajaran dan gerakan Ahmadiyah Qadian ke Indonesia 25 tidak lepas dari peran dari pelajar-pelajar Indonesia yang tengah menuntut ilmu di Qadian pada saat itu. Di antara kedua aliran tersebut, Ahmadiyah Qadian kerapkali ditentang oleh kebanyakan umat Islam dibandingkan dengan Ahmadiyah Lahore karena ajaranajarannya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti adanya nabi setelah Nabi Muhammad. Sementara itu, Ahmadiyah Lahore relatif bisa diterima umat Islam karena tidak menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi melainkan reformer agama (mujaddid). Kehadiran Ahmadiyah Qadian di Indonesia, dan di negara-negara yang mayoritas berpaham Sunni, seringkali menimbulkan penolakan yang berujung pada konflik sosial. Dalam hal ini, Ahmadiyah Qadian tidak jarang menjadi sasaran kekerasan dari sikap fundamentalisme keberagamaan masyarakat dalam melihat perbedaan penafsiran ajaran agama dengan Ahmadiyah Qadian. Keberadaan Ahmadiyah Qadian di pedesaan juga mengalami yang sama, mereka tidak lepas dari sasaran kekerasan sebagian masyarakat yang tidak bisa menerima ajaran mereka. Bila melihat ke belakang, kondisi ini tentu saja jauh dari kondisi yang ada sekarang di mana warga Ahmadiyah dan non Ahmadiyah hidup berdampingan dan saling menghargai. Rupanya berbagai faktor, seperti reformasi, intervensi pemerintah dalam bentuk regulasi, media massa dan fatwa MUI ikut membentuk perubahan suasana yang tadinya saling toleran dan menghormati menjadi saling curiga dan membenci satu sama lain. Akibatnya, kedua kelompok keagamaan ini di banyak pedesaan di Indonesia mengalami segregasi-segregasi akibat dari regulasi atau fatwa yang dikeluarkan pihak-pihak terkait. Interaksi di tengah masyarakat menjadi berjarak karena takut melanggar regulasi tersebut sehingga yang muncul adalah interaksi kepurapuraan. Tidak ada kohesifitas masyarakat pascaterjadinya konflik kedua kelompok keagamaan ini. Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) adalah sebuah organisasi keagamaan yang berafiliasi kepada Ahmadiyah Qadian. Organisasi keagamaan ini mendapat pengakuan dari negara berupa Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. JA.5/23/13. Pengakuan badan hukum Jemaat Ahmadiyah Indonesia ini dipertegas lagi oleh pernyataan Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26 0628/KET/1978 Tanggal 19 Juni 1978 yang menyatakan bahwa Jemaat Ahmadiyah Indonesia telah diakui sebagai badan hukum berdasarkan Statsblaad 1870 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan (Jemaat) Ahmadiyah adalah Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang secara teologis berafiliasi kepada Ahmadiyah Qadian. Pusat kegiatan keagamaan organisasi di Indonesia bertempat di Parung, Jawa Barat.