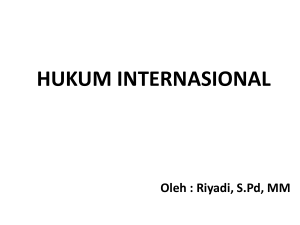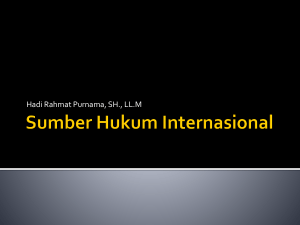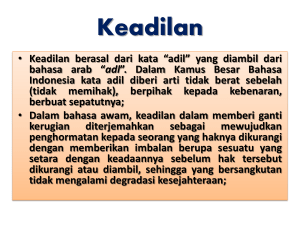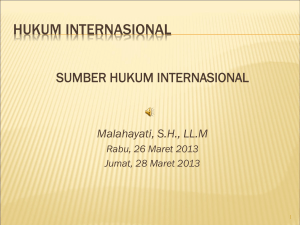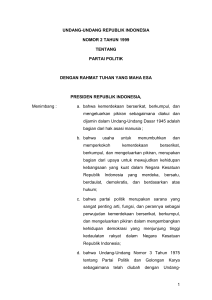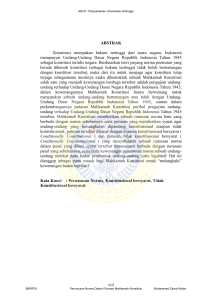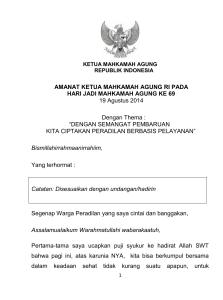pengujian peraturan perundang-undangan
advertisement

PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1 Oleh: Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH2 I. Pendahuluan Dalam pandangan Hans Kelsen,3 hukum adalah suatu hierarki mengenai hubungan normatif, bukan suatu hubungan sebab akibat dan esensinya adalah terletak pada “yang seharusnya ada (ought)” dan “yang ada (is)” (Sollen und sein).4 Oleh karena itu, kajian Kelsen tentang hukum adalah norma hukum (the legal norm), elemenelemennya, interelasinya, tatanan hukum secara keseluruhan strukturnya, hubungan tatanan hukum yang berbeda, dan kesatuan hukum dalam tatanan hukum positif yang majemuk. Realitas hukum adalah suatu fenomena yang lebih banyak dirancang sebagai “the positiveness of law”, dan dalam hal ini Kelsen membedakan dengan jelas antara “emperical law and transcedental justice by excluding the letter from specific concerns.”5 Hukum bukan manifestasi dari suatu “superhuman authorithy”, tetapi merupakan suatu teknik sosial berdasarkan pengalaman manusia. Konsekuensinya, dasar suatu hukum atau “validitasnya” bukan dalam prinsip-prinsip meta juristik, tetapi dalam suatu hepotesis juristik, yakni suatu norma dasar yang ditetapkan oleh “a logical analaysis of actual juristic thinking”. Dengan demikian, Kelsen tidak berbicara tentang hukum sebagai kenyataan dalam praktek, tetapi hukum sebagai disiplin ilmu, yakni apa yang terjadi dengan hukum dalam praktek berbeda dengan apa yang dipelajari dalam ilmu hukum, yang hanya mempelajari norma-norma hukum positif bukan aspek-aspek etis, politis, atau sosiologis yang dapat muncul dalam praktek hukum.6 Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa nilai validitas suatu hukum terletak pada kesesuainnya dengan norma lainnya terutama norma dasar. Dalam hubungan ini dapat dijelaskan bahwa norma dasar dapat dibedakan menjadi dua yaitu, norma statis dan 1 Disampaikan dalam Pelatihan Legal drafting di Kementerian Hukum dan HAM RI tanggal 13 November 2012. 2 Lulusan S3 Universitas Indonesia tahun 2006, menjadi Staf Pengajar Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta dan Staf Pengajar Fakultas Hukum pada beberapa Fakultas Hukum pada Perguruan Tinggi Swasta di Jakarta, Wakil Ketua Bidang Pendidikan Asosiasi Pengajar HTN/HAN, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi‟iyah, dan Panitera Mahkamah Konstitusi 2008 – 2010. 3 Hans Kelsen, General Theory Theory of Law and State, (New York: Russell & Russell, 1945), hal. 124. 4 Ibid, hal. 120.; Lihat W. Friedmann, Legal Theory, Fifth Edition(New York: Columbia University Press,1967), hal. 275 - 276 “ ... the science of law is hirarchy of normative relations, not a squence of causes and effect. ..... the most important foundation of Kelsen‟s theory, is essentially Neo Kantian, in so far as Kan had made the fundamental distinction between man as part of nature - subject to the laws of causation - and as a reasenable being wich regulates its conduct by imperative. This Produces the essential difference between “Ought” and “Is” (sollen und sein). 5 Hans Kelsen, Pure Theory of Law, (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1978), hal. xiii - xiv. Hal senada juga diuraikan oleh Joseph Raz, The Concept of a Legal System, Oxford: Oxford University Press, 1970). 6 Ibid, hal. 5 .... selanjutnya Kelsen menjelaskan bahwa: ".... The problem of law, as scientific problem, is the problem of social technique, not a problem of morals. The statement: " A certain social order has the character of law, is a legal order", does not imply the moral judgment that this order is good or just. There are legal orders wich are, from a certain point of view, unjust. Law and justice are two different concepts. Law is distinguished from justice is positive law. It is the concept of positive law wich is here in question; and a science of positive law must be clearly distinguished from a philosophy of justice. 1 norma dinamis. Norma statis merupakan norma yang telah memiliki validitas, sehingga seluruh isi norma tersebut ditaati dan diterapkan dalam kehidupan individu dan sosial. Setiap isi norma tersebut memiliki daya pengikat dan daya paksa, karena berasal dari norma dasar yang spesifik, memiliki validitas yang diyakini dan dipandang sebagai norma yang paling tinggi (akhir). Sifat statis, karena norma tersebut memiliki pengertian umum yang dapat dijadikan dalam membentuk norma khusus. Sedangkan norma dinamis, merupakan pembentukan norma dasar tertentu karena tidak ditemukan dalam norma statis, karena adanya perkembangan sosial, tetapi tidak dikaitkan dengan realitas sosial. Jika perkembangan sosial memiliki kehendak untuk mewujudkan suatu norma baru, maka pembentukannya tetap didasarkan pada norma dasar.7 Hal ini berarti otoritas pembentukannya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam norma dasar tersebut. Suatu norma merupakan bagian dari suatu sistem yang dinamis, jika norma tersebut telah dibuat menurut cara yang ditentukan oleh norma dasar. Deskripsi di atas menujukkan bahwa suatu norma hukum itu valid, karena dibuat menurut cara yang ditentukan oleh suatu norma hukum lainnya, dan norma hukum lainnya adalah landasan validitas norma hukum tersebut. Hubungan antara norma hukum yang mengatur pembentukan norma lain dengan norma lainnya sebagai hubungan antara “superordinasi” dengan “subordinasi” atau “superior dengan inferior norm” yang menunjukkan level atau hierarki norma. Norma yang menentukan pembentukan norma lainnya adalah norma yang lebih tinggi derajatnya, begitu sebaliknya, norma yang dibentuk tersebut derajatnya lebih rendah. Dalam hubungan ini, maka hubungan antara norma yang lebih tinggi dengan norma di bawahnya merupakan hubungan hierarki norma. Konsekuensinya adalah, bahwa norma yang lebih rendah derajatnya tidak dibenarkan bertentangan dengan norma di atasnya. Dengan demikian, suatu kesatuan hukum merupakan rangkaian hubungan hierarkis antara norma-norma yang satu dengan lainnya secara hierarkis tidak boleh bertentangan. Norma sebagai kesatuan nilai yang hidup dalam masyarakat memiliki kekuatan memaksa, dan ditaati, ketika norma tersebut telah ditempatkan sebagai pernyataan kehehendak, baik pernyataan kehendak individu maupun penyataan kehendak pembuat undang-undang. Penyataan kehendak tersebut diwujudkan baik dalam bentuk suatu transaksi hukum maupun dalam suatu undang-undang yang didalamnya mengandung unsur perintah atau keharusan untuk ditaati (validitas) dan diterapkan (efektifitas). Hal ini menujukkan bahwa setiap norma hukum memiliki unsur paksa, baik pada sisi pentaatan, maupun sisi penerapannya, dan untuk ini diperkenalkan unsur sanksi. Makna validitas norma hukum adalah bahwa setiap materi muatan norma hukum memiliki daya ikat dan paksa bagi subyek hukum tertentu dalam melakukan setiap perbuatan hukum. Sedangkan efektifitas norma hukum, berarti segi penerapan materi muatan hukum oleh organ yang memiliki otoritas untuk menerapkan suatu norma hukum. Jika terjadi suatu kasus pelanggaran terhadap suatu norma hukum, dan organ tersebut tidak mampu memberikan sanksi, maka norma hukum tersebut dapat dikatakan tidak efektif. Oleh karena itu, menurut Kelsen validitas dan efektifitas hukum 7 Hans Nawiasky, Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe, cet. kedua (Einsiedeln/Zurich/Koln: Benziger, 1948), hal.31 sebagaimana yang dikutip oleh A. Hamid Attamimi dalam, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara - Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I Pelita IV, disertasi yang dipertahankan di hadapan Senat Guru Besar Universitas Indonesia tanggal 12 Desember 1990 di Universitas Indonesia, hal. 288-289. 2 merupakan dua hal yang berbeda, yaitu validitas lebih bermuatan pada segi normatif, dan efektifitas lebih kepada proses penerapan norma. Landasan validitas suatu norma selalu dari norma, dan bukan dari fakta. Pencarian landasan validitas suatu norma bukan dari realita melainkan dari norma lain yang menjadi sumber lahirnya norma tersebut. Oleh karena itu, suatu norma yang validitasnya hanya dapat diperoleh dari norma yang lebih tinggi, Kelsen menyebut “norma dasar“.8 Norma dasar berfungsi sebagai rujukan dari setiap pembentukan norma, sehingga norma dasar juga sebagai sumber utama dan merupakan pengikat di antara norma-norma yang berbeda, dalam membentuk suatu tata normatif. Dalam pandangan ini, maka apabila suatu norma masuk dalam suatu tata norma tertentu, validitas atas norma tersebut dapat diuji oleh norma dasar tersebut. II. Hakekat Pengujian Peraturan Perundang-undangan Pengujian peraturan perundang-undangan secara terminologi bahasa terdiri dari perkataaan „pengujian‟ dan „peraturan perundang-undangan‟. Pengujian berasal dari akar kata ‟uji‟ yang memiliki arti percobaan untuk mengetahui mutu sesuatu, sehingga ‟pengujian‟ diartikan sebagai proses, cara, perbuatan, menguji. Sedangkan peraturan perundang-undangan diartikan sebagai peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dengan demikian pengujian peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai proses untuk menguji peraturan tertulis baik yang dibentuk oleh lembaga negara maupun pejabat yang berwenang yang memiliki kekuatan mengikat secara umum. Oleh karena itu, pengujian peraturan perundang-undangan yang diartikan sebagai suatu proses untuk menguji, akan berkaitan dengan „siapa‟ (subyek) dan „apa‟ (obyek) dalam proses pengujian peraturan perundang-undangan tersebut. Persoalan subyek dan obyek dalam perspektif pengujian peraturan perundang-undangan, dapat menimbulkan berbagai peristilahan yang kadang-kadang dan bahkan sering kali terjadi kekeliruan mengartikannya. Misalnya istilah toetsingsrecht dipersandingkan maknanya dengan judicial review. Kedua istilah tersebut memiliki perbedaan pengertian, karena toetsingsrecht memiliki arti lebih luas dan masih bersifat umum dan dapat dilekatkan pada lembaga kekuasaan negara baik, yudikatif, legislatif, maupun eksekutif.9 Sedangkan judicial review, cakupan dan ruang lingkupnya terbatas pada kewenangan pengujian yang dilakukan melalui mekanisme judicial dan lembaganya hanya dilekatkan pada lembaga kekuasaan kehakiman.10 8 . Hans Kelsen, General Theory ... op. cit., hal. 30 - 39 Bandingkan dengan Hans Nawiasky, sebagaimana yang dikutip oleh A. Hamid Attamimi dalam, op.cit., hal. 287-288. Dalam kaitan ini, norma dasar oleh Hans Nawiasky diartikan sebagai 'staatsfundamentalnorm' atau oleh Notonagoro disebut 'norma fundamental negara' yaitu, suatu norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi dari suatu negara termasuk norma pengubahannya. Hakekat hukum suatu 'staats-fundamentalnorm' adalah syarat bagi berlakunya suatu konstitusi atau undang-undang dasar. Oleh karena itu 'staatsfundamentalnorm' ada terlebih dahulu sebelum konstitusi atau undang-undang dasar. 9 Jimly Asshiddiqie, Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, (Jakarta: Konstitusi press, 2005), hal. 4 - 7 10 Ibid. Bandingkan Henry J. Abraham. The Judicial Process - An Introductory of the Court of The United States, England, and France, Third Edition Revised and enlarged (London: Oxford University Press, 1975) hlm. 280 yang menyatakan bahwa; "Judicial review is the power of any court to hold unconstitutional and hence unenforeable any law, any official action based upon a law, or any other action by a public official that it deems - upon careful, normally painstaking, reflection and the line with the canons of the thaught tradition 3 Di samping itu, perbedaan kedua istilah dalam pengujian peraturan perundangundangan tersebut juga terletak pada obyeknya. Oleh karena itu, agar tidak terjadi kesimpang siuran makna „toetsingsrecht‟ dan „judicial review‟ akan diuraikan batasan pengertian keduanya dalam penelitian ini. 1. Pengertian Toetsingsrecht dan Judicial Review dalam perspektif subyek dan obyek Pada umumnya istilah „toetsingsrecht‟11 diartikan sebagai „hak atau kewenangan untuk menguji‟ atau „hak uji‟.12 Pengertian tersebut memperjelas bahwa 'toetsingrecht' merupakan suatu proses untuk melakukan pengujian atau menguji dan secara harfiah dapat diartikan sebagai kewenangan untuk menguji.13 Pengertian menguji atau melakukan pengujian merupakan proses untuk memeriksa, menilai, dan memutuskan terhadap obyeknya. Pemahaman menguji atau melakukan pengujian dalam perspektif „toetsingsrecht‟ adalah memeriksa, menilai, dan memutuskan terhadap tingkat konstitusionalitas suatu peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi oleh suatu lembaga negara yang oleh undang-undang dasar dan/atau oleh undang-undang diberikan kewenangan.14 Pengertian „toetsingrecht‟ memang cukup luas, sehingga peristilahan yang timbulpun sangat tergantung dengan „subyek‟ dan „obyek‟ dalam pengujian tersebut. Jika dikaitkan dengan subyek, maka toetsingsrecht dapat dilekatkan pada lembaga kekuasaan negara yudikatif, legislatif, dan eksekutif.15 Jika hak atau kewenangan menguji tersebut diberikan kepada lembaga kekuasaan kehakiman atau hakim, maka of the law as well as judicial self restraint - to be conflict with the basic law - in the United States its constitution". 11 A. Teeuw, Kamus Indonesia - Belanda (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal.260 dan 842 yang menjelaskan bahwa toetsing diartikan pengujian, toetsen diartikan menguji dan recht diartikan hak atau hukum, sehingga toetsingrecht dapat diartikan sebagai kewenangan untuk menguji atau untuk melakukan pengujian. 12 Jimly Asshiddiqie, Model-model .. loc. cit. , hal. 7. 13 M.Laica Marzuki yang mengartikan toetsingsrecht sama dengan „hak menguj‟ yaitu, hak bagi hakim (atau lembaga peradilan) guna menguji peraturan perundang-undangan. Lihat M. Laica Marzki, Berjalanjalan di Ranah Hukum, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 67. 14 Sri Soemantri Martosoewignjo, Hak Menguji.. op.cit.,halm. 8. Dalam pengertian ini pengujian diartikan sebagai 'materiele teotsingsrecht.' Selain materiele teotsingsrecht, juga ada pengertian „formele teotsingrect‟ yang diartikan sebagai wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif seperti UU terjelma melalui cara-cara sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Ibid., hal. 6. Hal senada juga dinyatakan oleh Soedirjo, bahwa toetsingsrecht meliputi „materiele teotsingsrecht‟ dan „formele teotsingrect‟ yang keduanya memiliki makna yang sama sebagaimana yang dijelaskan oleh Sri Soemantri Martosoewignjo. Lihat Soedirjo, Mahkamah Agung - Uraian Singkat tentang Kedudukan, Susunan Kekuasaannya menurut UU No. 14 Tahun 985, (Jakarta: Media Sarana Press, 1987), hal. 63. Pengertian yang dijelaskan tersebut mengartikan „toetsingsrecht‟ dalam pengertian pengujian secara yudisial atau 'judicial review' dimaksudkan sebagai upaya yudisial untuk menilai konsistensi dan harmonisasi normatif secara vertikal, sehingga tidak terjadi konflik normatif secara vertikal untuk mewujudkan kepastian hukum. 15 Jimly asshiddiqie, Model-Model ... op.cit., hal 7. Dalam pengertian yang agak berbeda Paulus Effendi Lotulung mengartikan pengujian peraturan sebagai sebagai kontrol ekstern. yaitu kontrol yang dilakukan oleh badan-badan peradilan (judicial control) dalam hal timbul persengketaan atau perkara dengan pihak Pemerintah. Lihat Paulus Effendi Lotulung, Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap pemerintah, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal.xvi. 4 hal tersebut disebut „judicial review‟.16 Tetapi jika kewenangan tersebut diberikan kepada lembaga legislatif, maka istilahnya menjadi „legislative review‟17 dan demikian pula jika kewenangan dimaksud diberikan kepada lembaga eksekutif, maka istilahnya juga menjadi „executive review‟.18 Demikian pula pengertian toetsingsrecht jika dikaitkan dengan obyek dan waktu, maka hak menguji tersebut dilakukan secara „a posteriori‟, dan secara „a priori‟. Kewenangan untuk menguji secara „a posteriori‟, jika obyeknya adalah undang-undang atau setelah terjadinya tindakan atau perbuatan pemerintah, maka tindakan tersebut disebut „judicial review‟. Sedangkan kewenangan untuk melakukan pengujian secara „a priori‟, jika obyek yang diuji tersebut adalah Rancangan UndangUndang yang telah disetujui bersama tetapi belum diundangkan sebagaimana mestinya, maka hal tersebut disebut „judicial preview‟.19 Uraian di atas menunjukkan bahwa „toetsingsrecht‟ memiliki makna yang cukup luas, di samping tergantung subyek, obyek, juga tergantung kepada sistem hukum di tiap-tiap negara, termasuk untuk menentukan kepada lembaga kekuasaan negara mana kewenangan dimaksud akan diberikan. Dengan demikian, pengertian toetsingsrecht lebih luas di banding dengan judicial review. Penjelasan di atas menggambarkan bahwa pengertian toetsingsrecht dalam perspektif „judicial review‟ dapat diartikan sebagai „toetsingsrecht‟ dalam arti sempit atau uji judicial yang subyeknya tertentu yaitu lembaga kekuasaan kehakiman dan obyeknya juga tertentu yaitu peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur (regels). Dengan demikian dapat dibedakan dengan jelas bahwa toetsingsrecht dalam perspektif judicial review, legisltive review dan executive review dilihat dari segi subyeknya. Demikian pula dalam segi obyeknya, maka toetsingsrecht dalam perspektif judicial review obyek yang diuji adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur.20 Konsep toetsingsrecht dalam arti judicial review selanjutnya akan disebut „judicial review‟ merupakan bagian dari prinsip kontrol secara judicial atas produk 16 Ibid. Lihat Jerre S. Williams, Constitutional Analysis in a Nutshell, (St. Paul Minn: Weat Publishing co, 1979), hal. 1. yang menyatakan bahwa, „judicial review is a shorthand expression for the role court plays as the final authority on most, although not all, issues of the constitutionality of governmental acts.‟ Lihat Henry J. Abraham. The Judicial Process .. loc.cit., 17 Ibid., Bandingkan Oemar Seno Adjie, Kekuasaan kehakiman ... op.cit., hal 224-225, yang mengartikan legislative review sebagai peninjauan kembali produk hukum oleh lembaga pembuatanya yaitu, Presiden bersama-sama DPR. Dalam praktek ketatanegaraan Indonesia legislative review ini pernah dilakukan melalui Ketetapan MPRS No. XIX/MPR/1966 yang menugaskan kepada Pemerintah bersama-sama DPR untuk mengadakan peninjauan kembali (legislative review) terhadap produk legislatif (Presiden dan DPR) termasuk didalamnya Penpres, dan Perpres yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, termasuk di dalamnya adalah UU No. 19 Tahun 1964 dan UU No. 13 Tahun 1965. 18 Ibid. Jimly menggunakan istilah „executive review‟ untuk menjelaskan tentang kontrol normatif yang dilakukan oleh dan dengan cara-cara executive. Bandingkan Paulus Effendi Lotulung, Beberapa... op.cit., hal xvi. Paulus menggunakan istilah internal control, yaitu kontrol yang dilakukan sendiri oleh instansi pembuat peraturan. lihat John Adler dan Peter English, Judicial Review of the Execuitive, dalam 'Constitutional and Administrative Law' ( London: Macmillan Profesional Masters, 1989), hal. 289. 19 Paulus Effendi Lotulung, Ibid., hal. xvii. Jimly Ashiddiqie, Ibid., hal.8. 20 Dalam pengertian ini, maka jika obyek yang diuji adalah undang-undang terhadap UUD maka hal itu disebut „constitutional review‟, tetapi jika peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, maka disebut 'legal review' . Lihat Jimly Ashiddiqie, Ibid. 5 peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan dengan norma hukum secara hierarkis. Seperti yang dijelaskan dimuka, bahwa toetsingsrecht dalam arti judicial review dapat dilakukan, manakala prinsip kekuasaan negara menganut pemisahan kekuasaan atau „separation of power‟ dan „checks and balances‟.21 Kedua prinsip ini memungkinkan adanya keseimbangan posisi dan kekuasaan cabang-cabang kekuasaan negara seperti lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif dapat berjalan secara horisontal, dan memungkinkan masing-masing cabang kekuasaan negara tersebut dapat melakukan fungsinya sesuai yang diatur dan ditetapkan dalam undang-undang dasar dan/atau undang-undang. Seperti halnya Joseph Tanenhus merumuskan bahwa, judicial review adalah „the process with his a body judicial specify unconstitutional from action- what is done by legislative body and by executive head‟.22 Rumusan ini menggambarkan bahwa judicial review merupakan suatu proses untuk menguji tingkat konstitusionalitas suatu produk hukum badan legislatif atau badan eksekutif. Rumusan tersebut di atas mengindikasikan 3 (tiga) elemen pokok tentang judicial review yaitu, pertama, badan yang melaksanakan judicial review adalah badan/lembaga kekuasaan kehakiman; kedua, adanya unsur pertentangan antara norma hukum yang derajatnya di bawah dengan norma hukum yang derajatnya di atas; dan ketiga; obyek yang diuji adalah lingkup tindakan atau produk hukum badan legislatif dan ketetapan kepala eksekutif.23 Dengan demikian, kewenangan untuk melaksanakan „judicial review‟ adalah kewenangan badan kekuasaan kehakiman yang diberi kewenangan khusus untuk itu oleh undang-undang dasar dan/atau undang-undang, untuk menguji tingkat konstitusionalitas atau keabsahan suatu peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis derajatnya lebih tinggi.24 2. Obyek Pengujian Peraturan Perundang-undangan Obyek pengujian peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundangundangan yang bersifat mengatur (regeling), yaitu peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.25 21 Donald P. Kommers, Cross-National Comparations of Cnstitutional Court Toward a Theory of Judicial Review, Paper - presented at the annual meeting of the American Political Science Association, (Los Angeles, Calif, September 11, 1970). dalam Henry J. Abraham,The Judicial Process - An Introductory of the Court of The United States, England, and France, Third Edition Revised and enlarged (London: Oxford University Press, 1975) hlm. 281-283, menggambarkan bahwa judicial review sebagai doktrin hukum dapat dilaksanakan karena 5 faktor yakni (1) regime stability; (2) a competitive political party system; (3) significant horizontal power distribution; (4) a strong tradition of judicial indpendent, and (5) a high degree of political freedom. 22 Joseph Tanenhus, Judicial Review, entri dalam " An International Encyclopedia of the Social Sciences", (Macmillan, 1968). Bandingkan dengan Sri Soemantri yang mempersandingkan makna judicial review dengan pengertian hak uji materiel yang dirumuskan sebagai suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Sri Soemantri Martosoewignjo, Hak menguji ... op.cit., hal. 9. 23 Henry J. Abraham, The Judicial .. loc.cit., hlm. 280. Lihat Jerre S. Williams, Constitutional Analysis.. loc.cit., hal. 1-2. 24 AP. Le Sueur dan JW Herberg, Introduction to the Grounds of Judicial Review, dalam 'Constitutional and Administrative Law, (London, British Library Cataloguing in Publication Data, 1995), hal. 204. 25 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. 6 Untuk memahami peraturan perundang-undangan dapat diikuti pendapat Bagir Manan yang mengartikan peraturan perundang-undangan sebagai keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum dimana aturan tingkah laku tersebut berisi ketentuan-ketentuan tentang hak, kewajiban, fungsi, status dan suatu tatanan.26 Di samping bersifat umum, maka hal-hal yang diatur juga bersifat abstrak. Oleh karena itu, sifat umum dan abstrak menjadi ciri atau elemen dari peraturan peundang-undangan. Sifat umum dan abstrak yang dilekatkan sebagai ciri peraturan perundang-undangan, dimaksudkan untuk membedakan dengan keputusan tertulis pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang bersifat individual dan kongkrit yakni „ketetapan‟ atau „beschikking‟. Lebih lanjut Bagir Manan menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan memiliki 3 (tiga) unsur penting, yaitu: a. Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis, sehingga dapat juga disebut hukum tertulis; b. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ), yang memiliki wewenang membuat peraturan yang berlaku atau mengikat umum; c. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat secara umum.27 Sedangkan suatu keputusan itu dapat dikategorikan sebagai „ketetapan‟ atau „beshcikking‟ apabila memenuhi beberapa unsur, yaiu: a. keputusan sepihak; b. keputusan tersebut adalah tindakan hukum di lapangan hukum publik; c. keputusan dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha negara; d. keputusan mengenai masalah atau keadaan kongkrit dan individual; e. keputusan dimaksudkan untuk mempunyai akibat hukum tertentu yaitu, menciptakan, mengubah, menghentikan, atau membatalkan suatu hubungan hukum.28 Dengan demikian, dapat dibedakan antara keputusan yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur (regeling) dan mengikat secara umum dengan keputusan yang berbentuk beschikking. Dalam kaitan pengertian peraturan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum dan ketetapan yang bersifat kongkrit dan individual, Jimly lebih jelas dalam membedakan keduanya.29 Bahkan 26 Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, (Jakarta: Indo Hill Co, 1992) hl.3. Ibid. 28 Safri Nugaraha dkk, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2005), hal. 77. 29 Jimly Ashiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal 250 -254. Dalam penjelasannya bahwa suatu putusan dapat dikategorikan sebagai peraturan yang bersifat mengatur (regeling), pertama, kepentingan publik; kedua, menyangkut hubungan hukum atau hubungan hak dan kewajiban diantara sesama warga negara, dan antara warga negara dengan negara serta antara warga negara dengan pemerintah.Sedangkan beschikking merupakan keseluruhan „ketetapan‟ administratif yang dikeluarkan oleh pejabat publik yang dalam kapasitasnya diberikan kewenangan oleh UUD dan/atau UU untuk mengeluarkan ketetapan tentang sesuatu hal yang bersifat internal dan tidak bersifat publik, sehingga pengikatannya langsung kepada yang bersangkutan. Lihat M. Laica Marzuki, op.cit., hal. 110 - 111, yang menjelaskan bahwa paraturan perundang-undangan dapat dipahami dari segi fungsinya yaitu, pertama, berfungsi selaku norma (kaidah) guna menguji apakah suatu hak telah tepat secara hukum atau tidan; dan kedua, berfungsi selaku petunjuk (pedoman) guna tindakan yang bakal ditempuh oleh para pencari keadilan. Lebih jauh peraturan 27 7 pengertian peraturan perundang-undangan dirumuskan dengan batasan yang jelas, yaitu: “Dalam arti khusus pengertian peraturan perundang-undangan adalah keseluruhan susunan hirarkis peraturan perundang-undangan yang berbentuk UndangUndang ke bawah, yaitu semua produk hukum yang melibatkan peran lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah ataupun melibatkan peran pemerintah karena kedudukan politiknya dalam rangka melaksanakan produk legisltaif yang ditetapkan oleh lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah menurut tingkatannya masing-masing.”30 Dilihat dari segi jenis dan tata urutannya, Hamid Attamimi berpendapat dengan mengacu pada TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 dan menurut UUD 1945 (sebelum diubah), bahwa Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR tidak termasuk dalam kelompok peraturan perundang-undangan melainkan sebagai „Aturan Dasar‟ atau „Aturan Pokok Negara‟. Sedangkan yang termasuk peraturan perundangundangan adalah: Undang-Undang/Perpu, Peraturan pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Keputusan Kepala Badan Negara di luar jajaran Pemerintah yang dibentuk dengan undang-undang, Peraturan Daerah Tingkat I, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Peraturan Daerah Tingkat II, dan Keputusan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.31 Pendapat Hamid Attamimi mendapat kritikan dari Bagir Manan,32 sebagaimana yang dikemukakan, antara lain: a. apakah karakteristik suatu keputusan sebagai peraturan perundang-undangan ditentukan oleh sifat umum dan abstraknya norma, ataukah sifat muatannya yaitu, yang dasar/pokok dan tidak pokok; b. suatu jenis atau macam yang disebutkan tersebut dapat sekaligus sebagai peraturan perundang-undangan atau ketetapan (beschikking). Keputusan Presiden, Keputusan Menteri dan keputusan lain semacam itu tidak selamanya sebagai peraturan perundang-undangan; c. penyebutan keputusan Direktur Jenderal atau yang setara dengan itu sebagai suatu peraturan perundang-undangan, makin tidak menjelaskan kriteria untuk menentukan suatu keputusan termasuk peraturan perundang-undangan atau bukan; d. penyebutan secara berurutan sebagai suatu hubungan hierarki, akan menimbulkan pertanyaan, atas dasar apakah suatu Keputusan Menteri derajatnya lebih tinggi dari Keputusan Pemimpin Lembaga Pemerintahan Non Departemen. Begitu pula Peraturan Daerah Tingkat I derajatnya lebih tinggi dibanding dengan Peraturan Daerah Tingkat II. Dengan mengikuti pendapat Hamid Attamimi maupun Jimly Ashiddiqie, maka perundang-undangan tidak saja berfungsi meletakkan pengaturan normatif, tetapi juga merekayasa pembangunan dalam masyarakat. 30 Ibid, hal. 256 31 A. Hamid Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I - IV, Disertasi (Jakarta: Universitas Indonesia, 1990), hal.289. 32 Bagir Manan, Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-Undangan, Makalah disajikan pada Penataran Dosen dalam kegiatan Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung, 11 Nopember 1994, hal. 12 – 13. 8 Undang-Undang Dasar dalam hal ini UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak termasuk peraturan perundang-undangan melainkan sebagai „Aturan Dasar‟ atau „Aturan Pokok Negara‟ atau „Peraturan Dasar‟.33 Oleh karena itu, obyek pengujian peraturan perundangan-undangan dalam arti judicial review adalah segala bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur (regeling) dan mengikat secara umum. Dalam perspektif jenis dan tata urut peraturan perundangundangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pewraturan Perundangundangan. a. Obyek Pengujian: Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Undang-undang adalah suatu ketentuan tertulis yang dibuat oleh badan yang diberikan kewenangan oleh undang-undang dasar. Dalam konteks UUD Negara RI tahun 1945, maka undang-undang dibuat oleh DPR-RI dan Presiden, sehingga setiap rancangan undang-undang dibahas dan mendapat persetujuan bersama dari kedua lembaga tersebut. Dengan demikian, otoritas pembuatan undang-undang terletak di DPR tetapi proses dan penetapan suatu undang-undang berada pada DPR dan Presdien. Oleh karena itu, lembaga DPR merupakan lembaga politik yang salah satu fungsinya menurut UUD Negara RI tahun 1945 adalah di bidang legislasi.34 Perubahan pemegang otoritas pembentukan undang-undang yang semula berada pada Presiden dan beralih pada DPR dilakukan pada perubahan pertama UUD negara RI tahun 1945 pada tahun 1999 (19 Oktober 1999).35 Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran peran lembaga legislatif yang semula di bidang pembentukan undang-undang hanya ditempatkan sebagai lembaga persetujuan terhadap setiap rancangan undang-undang, dan selanjutnya diubah menjadi lembaga inisiator dalam pembentukan undang-undang. Oleh karena DPR adalah lembaga politik, dan setiap produk hukumnya juga merupakan proses politik, maka dengan sendirinya setiap pembentukan undang-undang, juga tidak terlepas dari intervensi dan kepentingan politik. Undang-undang sebagai proses politik, maka keputusan yang diambilpun tidak terlepas dari kekuatan-kekuatan politik yang mendukung/menyetujui dan/atau tidak menyetujui sehingga setiap pembentukan undang-undang tidak dapat menghindarkan diri dari „kekuatan mayoritas‟. Untuk menghindarkan ‟kekuatan mayoritas‟ yang tidak mempedulikan dan 33 Istilah UUD sebagai „Aturan Dasar‟ atau „Aturan Pokok Negara‟ merupakan istilah dari Hamid Attamimi, sedangkan Jimly Ashiddiqie menyebutnya sebagai „Peraturan Dasar‟. 34 Lihat Pasal 20 ayat (1) dan (2), Pasal 20A ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) UUD Negara RI tahun 1945. Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a UU. No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, yang menyatakan bahwa, DPR mempunyai tugas dan wewenang; a. bersama-sama Presiden membentuk undang-undang. UU No. 4 Tahun 1999 telah diubah dengan UU No. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPRdan DPRD yang diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 92 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4310. Menurut Pasal 25 UU No. 22 Tahun 2003 bahwa DPR mempunyai fungsi; a. legislasi, b. anggaran, c. pengawasan. Sedangkan Pasal 26 ayat (1) huruf a. UU No. 22 Tahun 2003 menyatakan DPR mempunyai tugas dan wewenang: a. membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 35 Perubahan pertama UUD Negara RI Tahun 1945 dilaksanakan oleh MPR-RI hasil Pemilu tahun 1999. Ketetapan MPR-RI tentang perubahan pertama UUD Negara RI tahun 1945 diambil pada tanggal 19 Oktober 1999 yang mengubah 9 pasal (15 ketentuan) yakni, Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 13 ayat (2) dan (3), Pasal 14 ayat (1) dan (2), Pasal 15; pasal 17 ayat (2) dan (3); Pasal 20 ayat (1) , (2), (3), dan (4); dan Pasal 21. 9 mengindahkan aspek kebenaran dan keadilan yang harus tercermin dalam setiap undang-undang serta konsistensi, sinkronisasi normatif secara vertikal, maka di perlukan suatu mekanisme hukum yakni proses pengujian materi undang-undang oleh suatu lembaga yang diberikan wewenang khusus untuk menjalankan pengujian. Seperti halnya pengalaman yang lalu yakni terbitnya UU No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman (Pasal 19) jelasjelas bertentangan dengan UUD 1945, dibiarkan tetap berlaku karena tidak ada lembaga yang mengontrol atau menguji atas kekeliruan tersebut. Oleh karena itu, sangat penting dan strategis posisi lembaga pengujian peraturan perundangundangan untuk melakukan kontrol normatif terhadap undang-undang agar tetap terjaga konsistensi, hamonisasi, sinkronisasi normatif secara vertikal, serta menjaga tertib hukum dan kepastian hukum. Undang-undang merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang jangkauan materi muatannya cukup luas, baik menyangkut kehidupan kenegaraan, pemerintahan, masyarakat dan individu. Bidang yang tidak dapat diatur oleh undang-undang hanyalah hal-hal yang sudah diatur oleh undang-undang dasar, atau yang oleh undang-undang itu sendiri telah didelegasikan pada bentuk peraturan perundang-undangan lain. Secara garis besar materi muatan36 suatu undangundang berkaitan dengan 2 (dua) hal pokok yaitu, pertama, mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar, dan yang kedua, karena diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar untuk diatur dengan undang-undang.37 Materi muatan suatu undang-undang menurut Bagir Manan didasarkan pada tolok ukur yang sifatnya masih umum, yaitu antara lain: 1) ditetapkan dalam undang-undang dasar; 2) ditetapkan dalam undang-undang terdahulu; 3) ditetapkan dalam rangka mencabut, menambah atau mengganti undangundang yang lama; 4) menyangkut hak dasar/hak asasi manusia; 5) menyangkut kepentingan atau kewajiban rakyat.38 Tolok ukur tersebut, dalam hal tertentu tidak bersifat mutlak, yakni tidak semua materi muatan tersebut harus diatur secara formal dalam suatu undang-undang, tetapi undang-undang yang bersangkutan dapat mendelegasikan pengaturannya kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.39 Oleh karena demikian luasnya materi muatan yang akan diatur dalam suatu undang36 Istilah 'materi muatan' diperkenalkan oleh A. Hamid Attamimi sebagai terjemahan dari 'het onderwerp', yaitu muatan yang sesuai dengan bentuk peraturan perundang-undangan tertentu. Lihat A. Hamid Attamimi, Peranan Keputusan Presiden .... op.cit., hal. 193. 37 Lihat Pasal 8 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan: Materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi hal-hal; a. mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 meliputi: 1. hak-hak asasi manusia; 2. hak dan kewajiban warga negara; 3. pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara; 4. wilayah negara dan pembagian daerah; 5. kewarganegaraan dan kependudukan; 6. keuangan negara. b. diperintahkan oleh suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. 38 Bagir Manan, Dasar-Dasar .... op.cit, hal. 37 – 40. 39 Ibid 10 undang, dan apabila dikaitkan dengan proses pembentukannya merupakan proses politik, maka kecenderungan untuk menempatkan berbagai kepentingan politik golongan tertentu sangat terbuka, bahkan kepentingan yang tidak sejalan baik dengan norma yang telah diatur dalam UUD maupun berbagai bentuk undangundang yang derajatnya sama masih dapat dilakukan. Dengan demikian, setiap keputusan politik, tidak selamanya memihak dan sejalan dengan prinsip- prinsip normatif, tetapi sangat terbuka dan rentan terhadap intervensi kepentingan politik sesaat. Untuk menghindarkan pengabaian prinsip konsistensi, sinkronisasi, dan harmonisasi normatif secara vertikal dan horizontal, maka diperlukan setiap produk hukum dari hasil keputusan politik, dapat diuji oleh lembaga tertentu yang diberikan kewenangan untuk itu oleh undang-undang dasar. Pengujian suatu undang-undang terhadap undang-udang dasar oleh Jimly disebut „pengujian konstitusional‟ atau „constitutional review‟, yaitu pengujian mengenai konstitusionalitas dari norma hukum yang sedang diuji (judicial review on the constitutionality of law).40 Pada umumnya pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar dilaksanakan pada negara-negara yang sistem pemerintahannya didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, prinsip negara hukum, prinsip pemisahan kekuasaan, dan prinsip hak asasi manusia. Hal ini berarti, pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar akan dapat dijalankan sebagaimana mestinya, jika dalam penyelenggaraan negara menganut prinsip „supremasi hukum‟ dan bukan „supremasi parlemen‟. Sebab dalam prinsip supremasi parlemen, maka produk hukum (UU) yang dihasilkan oleh Parlemen tidak dapat diganggu gugat, karena perlemen merupan representasi dari kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, posisi pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar menjadi penting dan strategis, karena 2 (dua) hal; pertama, untuk menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungannya dengan perimbangan peran antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif; dan kedua, untuk melindungi setiap warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin dalam konstitusi.41 Pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar dalam perspektif UUD 1945 (sebelum diubah) tidak dikenal, walaupun tidak ada satu ketentuan dalam UUD 1945 yang melarang dilakukannya pengujian tersebut. Hal ini disebabkan dianutnya prinsip pembagian kekuasaan yang mengarah pada praktek prinsip supremasi parlemen. Oleh karena itu, pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar pada dasarnya dapat dilaksanakan jika prinsip kekuasaan dalam negara menganut prinsip „pemisahan kekuasaan/ separation of power‟ dan prinsip „checks and balances‟ yang mengetengahkan praktek prinsip supremasi hukum. Pengujian peraturan perundang-undangan dengan obyek undang-undang terhadap undang-undang dasar baru diperkenalkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sejak tahun 2000 yaitu, melalui Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan: (1) Majelis Permusyawaratan Rakat berwenang menguji undang-undang terhadap UndangUndang Dasar 1945, dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 40 41 Jimly Asshiddiqie, Model-Model .... op.cit., hal. 8. Ibid, hal. 10-11. 11 Pasal 5 ayat (1) Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 dipahami bukan pengujian peraturan perundang-undangan dalam arti „judicial review‟, tetapi „legislative review‟, karena MPR merupakan lembaga perwakilan rakyat dan bukan lembaga judicial. Munculnya pengaturan ini adalah untuk menampung aspirasi yang muncul, agar setiap undang-undang tidak steril atau dapat diuji berkaitan dengan pengaturan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 2 Ketetapan MPR No. III/MPR/2000. Oleh karena UUD 1945 tidak mengatur tentang pengujian undang-undang dan lembaga pelaksananya, maka ditetapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara dan penjelmaan kedaulatan rakyat, sehingga logis jika produk hukum lembaga di bawahnya dapat diuji oleh MPR. Ketetapan MPR ini lahir, setelah 2 (dua) tahun dimulainya reformasi, termasuk reformasi politik dan hukum dan yang nampak adalah demokratisasi dalam penyelenggaraan negara dan sosial politik demikian kuatnya. Oleh karena UUD 1945 tidak ada ketentuan yang mengatur dan tidak melarang tentang pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, maka Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 tersebut dianggap suatu hal yang wajar dan diperlukan untuk membantu terlaksanakannya demokrasi yang masih dalam masa transisi. Dalam perkembangannya, pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar diatur secara jelas dalam Pasal 24C ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, dan Pasal UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar ini baru muncul sejak tahun 2000 dan langsung dibunyikan secara nyata dalam UUD dan undang-undang pelaksananya. Kelembagaan yang diberikan wewenang untuk melaksanakan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar adalah Mahkamah Konstitusi yang dibentuk tanggal 13 Agustus 2003. b. Obyek Pengujian: Peraturan Perundang-undangan di bawah undangundang terhadap undang-undang. Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (selanjutnya disebut pengujian peraturan di bawah undangundang), merupakan bentuk pengujian yang obyeknya adalah seluruh peraturan yang bersifat mengatur, abstrak dan mengikat secara umum yang derajatnya di bawah undang-undang. Bentuk dan tata urutannya sesuai yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 atau secara periodisasi sesuai dengan ketentuan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/21966, dan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000. Oleh karena itu, obyek yang diuji adalah segala peraturan di bawah undang-undang dan yang dijadikan tolok ukur pengujiannya adalah undangundang, maka oleh Jimly disebut „legal review‟ atau „judicial review on the legality of regulation‟. Pengujian peraturan perundang-undangan dengan obyek peraturan di bawah undang-undang, memang tidak diatur secara eksplisit dalam UUD 1945, tetapi sejak tahun 1970 secara eksplisit diatur dalam suatu undang-undang dan peraturan lainnya. Pertama kali diatur dalam Pasal 26 UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan dikuatkan oleh Pasal 11 Ketetapan MPR No. III/MPR/1978, serta Pasal 31 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pengaturan pengujian peraturan di bawah undang-undang ini 12 secara tidak langsung mempraktekkan prinsip „checks and balances‟ walaupun terbatas. Sebab pengujian peraturan pada dasarnya dapat dijalankan, apabila prinsip pemisahan kekuasaan dan „checks and balances‟ dianut dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan negara. Adanya pengaturan pengujian peraturan di bawah undang-undang ini juga dimaksudkan sebagai kontrol normatif setiap tindakan atau produk hukum yang berbentuk peraturan dari pihak eksekutif dalam hal ini Presiden dan lembaga negara lainnya. Hal ini disebabkan, Presiden oleh UUD 1945 diberikan tugas dan kewenangan yang cukup besar untuk menerjemahkan materi muatan suatu undang-undang dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Posisi Presiden dalam kaitannya dengan proses pembentukan dan pelaksanaannya cukup besar. Ketika undang-undang masih dalam proses, posisi Presiden adalah sebagai salah satu pihak pembahas dan pemberi persetujuan, di samping juga berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang. Selain itu, Presiden juga berhak dan berkewajiban untuk membuat dan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai instrumen pelaksanaan undang-undang. Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana undang-undang, maka dengan sendirinya tidak dapat dibuat untuk menjalankan UUD Negara RI Tahun 1945, karena instrumen hukum untuk menjalankan undang-undang dasar adalah undang-undang. Oleh karena itu, Peraturan pemerintah sebagai pelaksana undang-undang pada dasarnya materi muatannya adalah materi muatan undang-undang, tetapi lebih rinci. Oleh karena itu, posisi Presiden cukup besar dalam menafsirkan materi muatan undang-undang yang akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, di samping juga cukup besar pula intervensi politik bagi kepentingan Presiden. Di samping itu, Presiden juga dapat menerbitkan keputusan dalam bentuk peraturan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga negara. Untuk hal ini, maka wewenang yang melekat dan terlahir sebagai badan atau pejabat tata usaha negara yang didasarkan atas asas kebebasan bertindak (freis ermessen). Walaupun demikian, asas kebebasan bertindak untuk menjalankan pemerintahan tidak berarti bebas tanpa batas, tetapi tetap terikat oleh asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang layak, seperti asas persamaan perlakuan, asas kepastian hukum, dan asas dapat dipercaya. Dalam praktek, hal-hal tersebut dapat berupa Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, dan lain-lain. Sebagaimana tata urut peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah juga merupakan peraturan perundang-undangan walaupun jangkauan wilayah keberlakuannya terbatas pada wilayah yang bersangkutan (bersifat lokal). Oleh karena itu, Peraturan Daerah merupakan peraturan perundangundangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan sistem peraturan perundang-undangan secara nasional. Hal ini bearti, pembuatan suatu Peraturan Daerah bukan sekedar dikaitkan dengan kompetensi formal sebagai daerah otonom atau semata-mata hanya melihat dan didasarkan kepentingan daerah yang bersangkutan, tetapi lebih jauh harus didasarkan pada kesatuan penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan nasional secara keseluruhan. Prinsip ini yang berkaitan dengan prinsip kosnsitensi normatif secara vertikal, walaupun tetap terbuka pada keaneka ragaman materi muatan yang dituangkan 13 dalam Peraturan Daerah, tetapi tetap harus ada hubungan normatif secara vertikal. Dengan demikian, obyek pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang adalah Peraraturan pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Secara hierarkis, obyek pengujian peraturan di bawah undang-undang dapat dilihat dari perspektif bentuk dan tata urutan peraturan perundang-undangan yang diatur oleh Ketetapan MPRS/MPR, dan undangundang. III. Pengujian Peraturan di bawah Undang-Undang oleh Mahkamah Agung A. Pengaturan Pengujian Peraturan di bawah Undang-Undang. 1. Pengaturan Pengujian Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1993 Pada periode 1993 - 1998 pengaturan pengujian peraturan perundangundangan pada dasarnya diatur dalam Pasal 26 UU No. 14 Tahun 1970, Pasal 31 UU No. 1985, dan Pasal 11 Ketetapan MPR Tahun 1978. Ketiga Pada periode 1993 - 1998 pengaturan pengujian peraturan perundang-undangan pada dasarnya diatur dalam Pasal 26 UU No. 14 Tahun 1970, Pasal 31 UU No. 1985, dan Pasal 11 Ketetapan MPR Tahun 1978. Ketiga aturan tersebut secara umum menjadi dasar pelaksanaan pengujian peraturan perundang-undangan, tetapi ketiganya tidak mengatur teknis pelaksanaan pengujian peraturan perundang-undangan. Kelemahan yang nampak pada berbagai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan tentang pengujian peraturan perundang-undangan adalah tidak diikuti dengan pengaturan teknisnya, yaitu hukum acara pelaksanaan pengujian peraturan perundang-undangan. Mengingat demikian singkatnya ketentuan yang mengatur pengujian peraturan perundang-undangan, berdampak pada kesulitan Mahkamah Agung untuk melaksanakan fungsinya dalam pengujian peraturan perundangundangan. Untuk mengatasi kesulitan teknis pelaksanaan pengujian peraturan tesebut, maka Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 1993 (Perma No. 1 Tahun 1993).42 Di samping itu, lahirnya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1993 merupakan tafsir Mahkamah Agung terhadap ketentuan Pasal 26 ayat (2) jo. Pasal 31 ayat (3) U No. 14 Tahun 1985 yang menyatakan bahwa: „Putusan tentang pernyataan tidak syahnya peraturan perundangan tersebut dapat diambil berhubung dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi.‟ Dalam kaitan ini, terdapat dua kata yaitu, „putusan‟ dan „dapat‟ yang ditafsirkan bahwa, pertama, ketentuan tersebut menggunakan rumusan „putusan‟ dan bukan „penetapan‟, sehingga pemeriksaan perkara pengujian peraturan tersebut berupa putusan atau vonis sebagaimana dalam perkara contensiosa. Kedua, bahwa ketentuan dalam undang42 Perma No. 1 Tahun 1993 diterbitkan tanggal 11 Maret 1993, dikarenakan sejak diaturnya pengujian peraturan perundang-undangan belum diterbitkan hukum acara yang mengatur tentang pelaksanaan peradilan mengenai pengujian tersebut. Hal ini tercermin dalam dasar pertimbangan Perma No. 1 Tahun 1993 pada huruf b. Di samping itu, terbitnya Perma No. 1 Tahun 1993 juga sebagai antisipasi lebih lanjut atas permohonan pengujian peraturan perundang-undangan oleh Surya Paloh sehubungan dengan pencabutan SIUP harian Prioritas oleh Menteri Penerangan melalui penerbitan Peraturan Menteri Penerangan (PERMENPEN) No. 01 Tahun 1984 yang dianggap bertentangan dengan UU No. 11 Tahun 1966 tentang Pokok-Pokok Pers. Perkara ini telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tahun 1992 dengan Nomor: 01P/TN/1992 yang dibacakan tanggal 15 Juni 1993. 14 undang tersebut juga menggunakan kata „dapat‟ dan bukan kata „harus‟ atau „hanya dapat‟, sehingga ketentuan tersebut tidak bersifat limitatif, tetapi memberikan ruang alternatif. Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendirian bahwa gugatan perkara pengujian peraturan perundang-undangan dapat ditujukan langsung kepada Mahkamah Agung.43 Di samping itu, Perma No. 1 Tahun 1993 merupakan peraturan internal Mahkamah Agung untuk melaksanakan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan pasal 26 UU No. 14 Tahun 1970, Pasal 31 UU No. 14 tahun 1985, dan pasal 11 Tap. MPR No. III/MPR/1978. Di samping itu, Perma No. 1 Tahun 1993 juga sebagai pelaksanaan Pasal 79 UU No.14 Tahun 1985, sehingga Perma No. 1 Tahun 1993 dapat juga disebut „code of conduct‟ Mahkamah Agung dalam pengujian Peraturan perundang-undangan. Perma No. 1 Tahun 1993 secara substansial materi muatannya mengatur tata cara pengajuan gugatan hak uji materiil, Pemeriksaan di Persidangan, tentang putusan, pemberitahuan isi putusan, ketentuan lain, dan ketentuan penutup. Kelemahan yang masih terdapat dalam Perma No. 1 tahun 1993 adalah tidak mengatur secara tegas tentang pelaksanaan putusan yang memberikan sangsi atau batas waktu kepada instansi yang mengeluarkan peraturan untuk mencabut atau menggantinya. Memang ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 UU No. 14 Tahun 1970, dan Pasal 31 UU No. 14 tahun 1985 memberikan perintah kepada para pembuat peraturan yang mencabut atau merubahnya, tetapi tidak ada batas waktu sehingga dapat menyulitkan pelaksanaan putusan pengujian peraturan itu sendiri. Oleh karena itu, terbitnya Perma No. 1 Tahun 1993 memiliki nilai kesejarahan bagi pengujian peraturan perundang-undangan, disebabkan Mahkamah Agung berani melakukan langkah strategis dalam pembaharuan hukum, di samping meneguhkan atas posisi Mahkamah Agung sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengontrol produk hukum berupa peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Di samping itu, keberanian Mahkamah Agung untuk menerbitkan Perma No. 1 tahun 1993, juga dapat memberikan pencerahan terhadap pemerintah untuk lebih selektif dan hati-hati dalam memahami dan merumuskan ketentuan peraturan pelaksanaan undangundang. 2. Pengaturan Pengujian Peraturan Perundang-undangan Perubahan pertama UUD 1945 belum memberikan perubahan yang signifikan di bidang kekuasaan kehakiman terutama menyangkut pengujian peraturan perundang-undangan, dan baru pada perubahan ketiga UUD 1945 yang dilaksanakan dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2001 yang berpengaruh terhadap pengaturan pengujian peraturan perundang-undangan. Pengaturan pengujian peraturan perundang-undangan pada kurun waktu 1999 - 2004 dilakukan dalam bentuk Ketetapan MPR RI, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang serta Peraturan Mahkamah Agung. Pengaturan ini menunjukkan adanya dinamika politik hukum terhadap kekuasaan kehakiman khususnya 43 Sri Soemantri Martosoewignjo, laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Masalah Hukum Hak Uji Materiil, Badan Pembinaan Hukum Nasional - Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI, Tahun 1999/2000. 15 tentang pengujian peraturan perundang-undangan. Sebab setelah perubahan ketiga UUD 1945, maka hal-hal yang diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945 dengan sendirinya tidak berlaku lagi seperti ketentuan Pasal 5 ayat (1), dan ayat (2) Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. 1) Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 Lahirnya Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 bersamaan dengan perubahan kedua UUD 1945. Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 ini lahir sebagai penegasan terhadap prinsip supremasi hukum, walaupun dilahirkan oleh lembaga yang mencerminkan supremasi parlemen. Penegasan terhadap supremasi hukum ini memberikan peluang terhadap posisi kekuasaan kehakiman untuk diberikan kewenangan yang lebih luas dalam pengujian peraturan perundang-undangan. Perubahan terhadap perluasan kewenangan kekuasaan kehakiman tersebut belum dapat terwujud. Hal ini dikarenakan dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/ 2000 dalam hal pengaturan pengujian peraturan perundang-undangan masih menganut „toetsingrecht‟ dalam pengertian „legislative review‟ dan „judicialreview‟ sekaligus,44 walaupun lembaga pelaksananya berbeda yakni MPR dan Mahkamah Agung. Kedua pengertian tersebut dapat ditelaah pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Ketetapan MPR No. III/MPR/2000. Munculnya dua pengertian sekaligus tersebut menunjukkan adanya transisi politik hukum yang mengedepankan supremasi konstitusi dengan yang mempertahankan supremasi parlemen. Secara normatif dapat ditelaah bunyi Pasal 5 ayat (1) dan (2) Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 yaitu; (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (2) Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Ketetapan MPR di atas menunjukkan bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan representasi dari kedaulatan rakyat merupakan satu-satunya lembaga pentafsir konstitusi. Walaupun MPR bukan lembaga judicial melainkan lembaga politik, tetapi karena posisinya menurut UUD 1945 merupakan lembaga tertinggi negara, maka dianggap wajar jika MPR sebagai lembaga atau subyek yang diberi kewenangan untuk menguji undangundang terhadap undang-undang dasar.Tetapi apa yang dilakukan oleh MPR berkaitan dengan kewenangan yang diberikan oleh pasal 5 ayat (1) tidak harus dipahami sebagai „toetsingrecht dalam arti judicial review‟, tetapi toetsingrecht dalam pengertian „legislative review‟.45 44 MPR bukan lembaga kekuasaan kehakiman tetapi MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang merepresentasikan kedaulatan rakyat, sehingga MPR adalah lembaga legislatif. Pemberian pengujian kepada MPR berarti ketentuan Pasal 5 ayat (1) Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 memberikan kewenangan kepada lembaga pembuatnya untuk melakukan pengujian dan diklasifikasikan sebagai legislative review. 45 Jimly Asshiddiqie, Model-Model .... loc.cit,, hal. 8. 16 Oleh karena itu, menempatkan MPR sebagai lembaga yang berwenang untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar pada hakekatnya tidak harus dipersalahkan, karena selain memang UUD 1945 tidak mengaturnya secara jelas, maka MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat dapat memposisikan sebagai lembaga yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan. Tetapi jika dikaitkan dengan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, maka kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan tersebut memang tidak ada, sehingga kewenangan itu dapat dikategorikan sebagai „legislative review‟, karena yang diuji adalah produk hukum lembaga legislatif bersama eksekutif yang derajatnya di bawah Ketetapan MPR dan yang menguji (MPR) pada hakekatnya adalah lembaga legislatif. Adapun ketentuan Pasal 5 ayat (2) merupakan replikasi dari ketentuan Pasal 11 Ketetapan MPR No. III/MPR/1978, Pasal 26 UU No. 14 Tahun 1970 dan pasal 31 UU No. 14 Tahun 1985. Oleh karena itu, ketentuan pasal 5 ayat (2) yang menempatkan Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dipahami sebagai „toetsingrecht‟ dalam arti „judicial review‟, karena Mahkamah Agung RI merupakan lembaga judicial dan obyeknya adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh institusi/pejabat politik yang diberikan kewenangan oleh UUD dan/atau undang-undang. Dengan demikian, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) mengandung 2 (dua) makna, yaitu „legislative review‟ yang diberikan kepada MPR RI, dan makna „judicial review‟ yang kewenangannya diberikan kepada Mahkamah Agung RI. 2) Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan UUD Negara RI tahun 1945, secara langsung berpengaruh dalam bidang kekuasaan kehakiman. Dalam hal kekuasaan kehakiman, maka Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945 telah diubah, baik segi kelembagaan, kewenangan, tugas dan fungsinya. Di samping itu, ketentuan tersebut juga telah mengakhiri perdebatan panjang tentang kewenangan menguji peraturan perundang-undangan yang diawali ketika merumuskan Pasal 24 UUD 1945, dilanjutkan ketika merumuskan Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-Ketentuan Pokok kekuasaan kehakiman sampai dengan tahun 2000 dan berakhir pada tahun 2001. Ketentuan tersebut juga menghapus ketentuanketentuan tentang pengujian peraturan perundang-undangan dalam berbagai peraturan. Penjabaran teknis dari ketentuan-ketentuan tersebut akan diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Apabila diamati dengan seksama, ketentuan Pasal 24A ayat (1) dan pasal 24C ayat (1) terkesan ada dualisme dalam penanganan pengujian peraturan perundang-undangan yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, dan yang membedakan hanyalah tingkatan obyek yang diuji. Pembagian yang demikian memang tidak ideal, karena menimbulkan perbedaan atau putusan yang saling bertentangan antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung. Terlepas dari kelemahan tersebut untuk sementara waktu pembagian yang demikian diterima dan dipraktikkan dulu pada tahap awal pertumbuhan lembaga Mahkamah Konstitusi di Indonesia, tetapi kedepan, memang harus dipikirkan kemungkinan mengintegrasikan seluruh sistem pengujian peraturan di bawah kewenangan 17 Mahkamah Konstitusi. 3) Pengaturan Pengujian peraturan perundang-undangan dalam berbagai Undang-Undang. Perubahan yang mendasar tentang kekuasaan kehakiman akibat dari perubahan ketiga UUD negara RI tahun 1945 sebagaimana diuraikan di atas, maka pengujian peraturan perundang-undangan diatur kembali dalam berbagai undang-undang yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yaitu UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pengaturan pengujian peraturan perundang-undangan dalam UU No. 24 Tahun 2003 dapat dilihat pada pasal yang mengatur tentang kewenangan dan kewajiban yang melekat pada Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003 adalah sebagai berikut: (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : a. menguji undang-undang terhadap UUD Negara RI Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara RI tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD negara RI Tahun 1945. Dengan demikian, munculnya Mahkamah Konstitusi yang secara kelembagaan merupakan lembaga negara yang kedudukannya sederajat dengan lembaga negara lainnya dan pengaturannya terdapat dalam UUD Negara RI Tahun 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003, merupakan bagian dari upaya kontrol yudisial terhadap penyelenggaraan negara melalui mekanisme hukum. Mekanisme kontrol oleh lembaga kekuasaan kehakiman merupakan bagian penting dalam upaya membangun dan mengembangkan prinsip negara demokrasi berdasar atas hukum atau negara hukum yang demokratis. Demikian pula Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan unifikasi dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang No. 35 tahun 1999 tentang perubahan UU No. 14 Tahun 1970. Terbitnya UU No. 4 Tahun 2004 merupakan konsekuensi yuridis atas perubahan UUD Negara RI Th. 1945 di bidang kekuasaan kehakiman yaitu, Pasal 24 ayat (2), Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1). Secara normatif, pengujian peraturan perundangundangan juga diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, yaitu dalam Pasal 2, Pasal 11 ayat (2) huruf b, dan pasal 12 ayat (1) huruf a. Pasal 2 UU No. 4 tahun 2004 menjelaskan bahwa, “Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung 18 dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi” Pasal 11 ayat (2) huruf b UU No. 4 Tahun 2004 menjelaskan bahwa; “Mahkamah Agung mempunyai kewenangan: ... menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang ..” Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU No. 4 Tahun 2004, menjelaskan bahwa; “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:... a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Demikian pula dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang mahkamah Agung, dapat dilihat pada Pasal 31 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) sebagai berikut: (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. (3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung. (4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan. (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan. Sedangkan Pasal 31A sebagai pasal tambahan mengatur tentang tata cara pengajuan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan oleh pemohon langsung kepada Mahkamah Agung. Oleh karena itu, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diatur dalam Pasal 31 dan 31A UU No. 5 Tahun 2004 melalui 2 (dua) cara yaitu, pertama, melalui pemeriksaan pada tingkat kasasi (ada gugatan), dan kedua, melalui permohonan langsung ke Mahkamah Agung. Dengan demikian pengaturan pengujian peraturan perundang-undangan telah lengkap yakni mulai dari UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, UU No. 24 tahun 2003, UU No. 4 Tahun 2004 dan UU No. 5 Tahun 2004 dan lembaga pelaksananya adalah Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Konstitusi RI. 3. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1999 Demikian pula di bidang pengujian peraturan perundang-undangan juga terjadi perubahan yang cukup mendasar yaitu diperkenalkannya prosedur 19 „Permohonan‟46 yang dalam ketentuannya tidak diatur dalam Pasal 26 UU No. 14 Tahun 1970, Pasal 31 UU No. 14 tahun 1985, dan Pasal11 Tap. MPR No. III/MPR/1978.Terbitnya peraturan tersebut memberikan nilai kesejarahan terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman dan khususnya pelaksanaan pengujian peraturan perundang-undangan. Seperti halnya perma No. 1 Tahun 1993, maka terbitnya Perma No. 1 Tahun 1999 merupakan perluasan dari materi Perma No. 1 Tahun 1993. perluasan materi muatan yang mendasar adalah prosedur pengajuan perkara pengujian yang semula hanya dikenal melalui gugatan juga dapat melalui permohonan. Dalam hubungan ini, maka dalam Perma No. 1 tahun 1999 memberikan alternatif terhadap prosedur pengajuan perkara pengujian peraturan perundang-undangan, yakni dapat melalui gugatan dan melalui permohonan. Prosedur permohonan sebagai salah satu alternatif pilihan didasarkan pemikiran bahwa secara sosiologis sebagai upaya untuk menampung aspirasi hukum yang berkembang dalam masyarakat seiring dengan semangat reformasi untuk menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta pelaksanaan reformasi di bidang hukum sebagaimana yang diamanatkan Ketetapan MPR No. X/MPR/1998.47 Penerbitan perma No. 1 tahun 1999 ini juga dinilai langkah maju dan berani Mahkamah Agung untuk lebih terbuka kepada semua pihak yang menilai adanya peraturan-peraturan di bawah undang-undang yang diterbitkan oleh para pejabat publik yang dianggap bertentangan dengan undang-undang untuk diajukan pengujian ke Mahkamah Agung, baik melalui prosedur gugatan maupun permohonan. Di samping itu, menurut Sri Soemantri, bahwa penerbitan Perma No. 1 Tahun 1999 juga langkah strategis Mahkamah Agung yang menghendaki perlunya diberikan kewenangan yang lebih luas untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan, tidak hanya obyek peraturan di bawah undangundang, melainkan juga undang-undang terhadap undang-undang dasar. Pemberian wewenang tersebut dapat ditempuh melalui Penjelasan Pasal 26 UU No. 14 Tahun 1970 yaitu dengan ketetapan MPR. Di samping itu, semua putusan pengujian peraturan perundang-undangan diumumkan dalam Berita Negara, sehingga masyarakat dapat mengetahui status peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Demikian dalam Perma No. 1 Tahun 1999 ini, juga diatur tentang pelaksanaan putusan pengujian yang semula diserahkan kepada instansi pembuatnya juga diberikan batas waktu pencabutan atau perubahannya. Jika dalam waktu yang telah ditentukan itu instansi yang bersangkutan tidak mencabutnya, maka demi hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak memiliki kekuatan hukum.48 Ketentuan tersebut di atas, memberikan dasar pijak yang kuat kepada Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam perkara pengujian peraturan perundang-undangan. Semua keputusan pengujian peraturan 46 Prosedur pengajuan perkara pengujian peraturan perundang-undangan melalui 'permohonan' diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materiil yang ditetapkan tanggal 20 Mei 1999. Dengan berlakunya Perma No. 1 Tahun 1999, maka Perma No. 1 Tahun 1993 dinyatakan tidak berlaku. 47 Lihat konsideran sebagai dasar pertimbangan pada huruf c Perma No. 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materiil. 48 Lihat Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 1999. 20 perundang-undangan diwajibkan untuk diumumkan melalui Berita Negara yang semula hal ini tidak diatur. Di samping itu, ditentukan batasan waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mencabut peraturan perundang-undangan tersebut, dan jika tidak dicabut juga, maka dinyatakan tidak berlaku secara otomatis. Dengan demikian, ketentuan Pasal 12 dan 13 Perma No. 1 tahun 1999 cukup maju dan mencerminkan betapa kuatnya hukum untuk memaksa subyek hukum untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum. Hal ini juga tercermin komitmen terhadap penegakan negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum. B. Prosedur Pengujian Peraturan perundang-undangan 1. Prosedur Pengajuan Gugatan dan Permohonan Prosedur pengajuan pengujian peraturan perundang-undangan tidak diatur dalam berbagai undang-undang yang mengatur tentang pengujian peraturan di bawah undang-undang sebagaimana yang dijelaskan di atas, melainkan pengaturannya melalui Peraturan Mahkamah Agung. Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung tentang Hak Uji Materiil tersebut di atas, adalah untuk melaksanakan perintah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ketetapan MPR dan Undang-Undang lainnya. Secara eksplisit ketentuan teknis pelaksanaan pengujian peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Mahkamah Agung hanya diatur dalam Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985,49 maka dengan sendirinya Mahkamah Agung diberikan wewenang untuk menerbitkan peraturan yang bersifat internal. Untuk itu, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 1993 dan diperbaharui dengan Perma No. 1 Tahun 1999. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 1993 memuat pengaturan tentang prosedur pengajuan hak uji materiil, pemeriksaan persidangan, putusan dan pemberitahuan putusannya. Ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam Perma No. 1 Tahun 1993 merupakan ketentuan khusus sebagai penjabaran dan pelaksanaan perintah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengujian peraturan peraturan perundang-undangan. a. Menurut PERMA No. 1 Th. 1993 1) Gugatan ditujukan kepada Badan/Pejabat Tata usaha negara yang menerbitkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, ditanda tangani penggugat atau kuasa hukumnya, dapat diajukan secara langsung ke Mahkamah Agung atau melalui pengadilan tingkat I di wilayah hukum tergugat, dengan menyebutkan sejelas-jelasnya alasan gugatan, dan dibuat rangkap tiga; 2) Gugatan Hak Uji Materiil yang diajukan secara langsung ke Mahkamah Agung, apabila sudah memenuhi persyaratan formal administratif, didaftar dalam buku register khusus oleh Direktur Tata 49 Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 menyatakan :‟Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut halhal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang ini‟. Ketentuan ini dalam perkembangannya juga diatur dalam pasal 31 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2004. tentang Mahkamah Agung. 21 Usaha Negara Mahkamah Agung RI. Gugatan yang diajukan melalui pengadilan tingkat I, apabila sudah memenuhi persyaratan formal administratif, didaftar oleh Panitera Kepala pengadilan tersebut, selanjutnya berkasnya dikirimkan ke Direktur Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI untuk didaftar, dan kepada penggugat atau kuasanya diberikan tanda terima berkas perkaranya. 3) b. 50 51 Direktur Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI memeriksa kelengkapan berkas perkaranya, dan apabila ada kekurangan lengkapan dapat langsung atau melalui pengadilan tingkat I yang bersangkutan dan meminta penggugat atau kuasanya untuk melengkapinya. Jika berkas perkara telah lengkap, Direktur Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI mengajukan ke Ketua Mahkamah Agung.50 Menurut PERMA No. 1 Tahun 1999 Prosedur pengajuan perkara pengujian peraturan dibawah undangundang terhadap undang-undang menurut Perma No. 1 Tahun 1999 dapat dilakukan melalui ‟gugatan‟ dan ‟permohonan‟51. Secara rinci prosedur pengajuan pengujian peraturan dibawah undang-undang terhadap undangundang menurut Perma No. 1 Tahun 1999 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Prosedur Gugatan (1) Gugatan dapat diajukan kepada Mahkamah Agung dengan cara: a. langsung ke Mahkamah Agung, dan b.melalui Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat kedudukan tergugat. (2) Gugatan hanya dapat diajukan terhadap satu peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap peraturan perundangundangan yang saling berkaitan secara lansung. (3) Gugatan dibuat rangkap seperlunya dengan menyebutkan sejelas-jelasnya alasan-alasan yang dijadikan dasar gugatannya dan harus ditanda-tangani oleh Penggugat atau kuasanya yang sah. (4) Gugatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak berlakunya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. (5) Penggugat membayar biaya perkara pada saat mendaftarkan gugatan yang besarnya akan diatur tersendiri. Selanjutnya, tata cara atas proses gugatan pengujian tersebut apabila diajukan langsung ke Mahkamah Agung sebagai berikut: (1) Dalam hal gugatan diajukan langsung ke Mahkamah Agung, didaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung dan dibukukan dalam buku register tersendiri dengan menggunakan kode: .... Lihat Pasal 1 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1993. Lihat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1999. 22 G/HUM/Th...... (2) Panitera Mahkamah Agung memeriksa kelengkapan berkas dan apabila terdapat kekurangan dapat meminta langsung kepada penggugat atau kuasanya yang sah. (3) Panitera Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan gugatan tersebut kepada pihak tergugat setelah terpenuhi kelengkapan berkasnya. (4) Tergugat wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan gugatan tersebut. (5) Panitera Mahkamah Agung menyampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk ditetapkan Majelis Hakim Agung setelah lengkap berkas gugatan tersebut. Selanjutnya apabila gugatan tersebut diajukan melalui Pengadilan, maka tatacaranya sebagai berikut: (1) (2) (3) (4) (5) (6) 2) Dalam hal gugatan diajukan melalui Pengadilan Negeri setempat, didaftarkan pada kepaniteraan dan dibukukan dalam buku register perkara tersendiri dengan menggunakan kode: .......G/HUM/Th...../PN..... setelah Penggugat atau kuasanya yang sah membayar biaya perkara dan diberikan tanda terima biaya perkara tersebut. Panitera pengadilan Negeri memeriksa kelengkapan gugatan yang telah didaftarkan oleh Penggugat atau kuasanya yang sah. Panitera Pengadilan Negeri sebelum meneruskan berkas gugatan kepada Mahkamah Agung terlebih dahulu wajib mengirimkan salinan gugatan kepada tergugat untuk mendapatkan jawaban atas gugatan Penggugat. Tergugat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan gugatan tersebut harus mengirim atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Pengadilan negeri yang bersangkutan. Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan segera mengirimkan kepada Mahkamah Agung pada hari berikutnya setelah tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (4). Panitera Mahkamah Agung menyampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk ditetapkan Majelis Hakim Agung. Prosedur Permohonan Prosedur „permohonan‟ tidak terdapat dalam rumusan berbagai ketentuan tentang pengujian peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 UU No. 14 tahun 1970, pasal 31 UU No. 14 Tahun 1985 dan Pasal 11 Tap. MPR No. III/MPR/1978. Jika ditelusuri ketentuan Pasal 26 ayat (2), Pasal 31 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1985, maka keduanya menggunakan kata hasil pengujian. Hal ini berarti semua perkara pengujian merupakan perkara ‟contentieus‟, sehingga penyelesaian akhir dengan ‟putusan‟ hakim. Secara konseptual putusan adalah suatu penyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, 23 diucapkan di persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.52 Dalam sengketa suatu perkara dapat dibedakan terdapat 2 (dua) hal yaitu, perkara yang bersifat ‟contentieus‟53 atau sengketa yang berasal dari gugatan, dan perkara yang bersifat ‟voluntair‟54 atau sengketa yang berasal dari permohonan. Jenis putusannyapun berbeda yaitu, untuk perkara ‟contentieus‟, maka jenis putusannya disebut ‟putusan‟, sedangkan untuk perkara ‟voluntair‟, maka jenis putusannya disebut ‟penetapan‟.55 Oleh karena itu, prosedur ‟permohonan‟ yang diatur dalam Perma No. 1 Tahun 1999 tidak harus dinilai sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang, sebab dalam ketentuan tersebut juga tidak diatur pelarangan prosedur ‟permohonan‟, tetapi justeru didasarkan pada alasan sosiologis, dimana masyarakat lebih banyak menggunakan prosedur ‟permohonan‟. Prosedur ‟permohonan‟ perkara pengujian peraturan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Permohonan keberatan diajukan kepada Mahkamah Agung dengan cara: a. langsung ke Mahkamah Agung, dan b. melalui Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat kedudukan Pemohon. (2) Permohonan keberatan hanya dapat diajukan terhadap satu peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan secara langsung. (3) Permohonan keberatan dibuat rangkap seperlunya dengan menyebutkan sejelas-jelasnya alasan-alasan yang dijadikan dasar keberatannya dan wajib ditanda-tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah. (4) Permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak berlakunya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. (5) Pemohon membayar biaya permohonan pada saat mendaftarkan permohonan keberatan yang besarnya diatur tersendiri. Apabila pengajuan ‟permohonan‟ tersebut dilakukan langsung kepada Mahkamah Agung, maka prosesnya adalah sebagai berikut: 52 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, cet. kelima (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal.173. 53 Contentieus diartikan sebagai perkara sengketa yang berasal dari gugatan artinya perkara itu timbul karenan adanya gugatan untuk menyelesaikan perselisihan anatara dua atau lebih pihak kepada pengadilan. Lihat Sudikno Martokusumo, Ibid. hal 74. 54 Voluntair diartikan sebagai sengketa yang berasal dari permohonan, artinya perkara itu timbul karena permohonan pihak tertentu atas pihak lainnya atau para pihak untuk ditetapkan status hukumnya. seperti permohonan penetapan waris, permohonan ikrar talaq dalam hukum perkawinan. Lihat Sudikno Martukusumo, ibid. 55 Ibid, hal. 174. 24 (1) (2) (3) Dalam hal permohonan keberatan diajukan langsung ke Mahkamah Agung, didaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung dan dibukukan dalam buku register tersendiri dengan menggunakan kode: .....P/HUM/Th.... Panitera Mahkamah Agung memeriksa kelengkapan berkas dan apabila terdapat kekurangan dapat meminta langsung kepada Pemohon atau kuasanya yang sah. Panitera Mahkamah Agung menyampaikan kepada ketua Mahkamah Agung untuk ditetapkan Majelis Hakim Agung, setelah lengkap berkas permohonan keberatan tersebut. Demikian pula, apabila pengajuan ‟permohonan‟ tersebut dilakukan melalui Pengadilan Negeri, maka prosesnya adalah sebagai berikut: (1) Dalam hal permohonan keberatan diajukan melalui Pengadilan Negeri setempat, didaftarkan pada kepaniteraan dan dibukukan dalam buku register perkara tersendiri dengan menggunakan kode: .......P/HUM/Th...../PN..... setelah Pemohon atau kuasanya yang sah membayar biaya permohonan dan diberikan tanda terima. (2) Panitera pengadilan Negeri memeriksa kelengkapan permohonan keberatan yang telah didaftarkan oleh Pemohon atau kuasanya yang sah, dan apabila terdapat kekurangan dapat meminta langsung kepada Pemohon atau kuasanya yang sah.56 (3) Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan segera mengirimkan kepada Mahkamah Agung pada hari berikutnya. (4) Panitera Mahkamah Agung menyampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk ditetapkan Majelis Hakim Agung. 2. Pemeriksaan dalam Persidangan Ketentuan yang mengatur tentang tatacara pemeriksaan atas, baik gugatan maupun permohonan pengujian peraturan dibawah undang-undang terhadap undang-undang secara eksplisit sebagai berikut: (1) Ketua Mahkamah Agung RI menetapkan Majelis yang akan memeriksa dan memutus baik gugatan maupun permohonan pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. (2) Majelis Hakim Agung memeriksa dan memutus gugatan tentang hak uji materiil tersebut dengan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku bagi perkara gugatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sesuai dengan azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. (3) Majelis Hakim Agung memeriksa dan memutus permohonan keberatan tentang hak uji materiil tersebut dengan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku bagi perkara permohonan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sesuai dengan azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. 56 Lihat Pasal 7 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 1999 25 Proses pemeriksaan yang ditentukan dalam Perma No. 1 tahun 1993 dengan Perma No. 1 Tahun 1999, pada prinsipnya tidak berbeda dan hanya dibedakan dengan perkara permohonan keberatan yang tidak diatur atau dikenal dalam Perma No. 1 tahun 1993, tetapi diatur dalam Perma No. 1 Tahun 1999. Pemeriksaan perkara pengujian, baik melalui gugatan maupun melalui permohonan keberatan kesemuanya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi perkara gugatan57 atau permohonan58 dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Oleh karena yang diperiksa, dinilai dan diputuskan bukanlah suatu peristiwa kongkrit yang dilakukan oleh subyek hukum, melainkan suatu norma hukum yang mengikat secara umum, sehingga dampaknya berdimensi multi baik normatif, maupun politik, sosial, ekonomi bahkan budaya, maka prinsip kehatihatian dan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan juga diperlakukan bagi perkara pengujian. 3. Putusan Sebagaimana yang dijelaskan di atas, bahwa Pasal 31 ayat (2) UU No. 14 tahun 1985 dan perma No. 1 tahun 1993 dan perma No. 1 Tahun 1999 menggunakan kata „putusan‟ dan bukan kata ‟penetapan‟. Kata „putusan‟, merupakan ‟vonis‟ Hakim atau Majelis Hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang bersifat ‟contentieus‟, dan kata ‟penetapan‟ dipakai dalam perkara yang bersifat ‟voluntair‟ atau melalui ‟permohonan‟. Oleh karena dalam ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan Perma No. 1 tahun 1993 dan Perma No. 1 tahun 1999 menggunakan kata „putusan‟, maka dengan sendirinya ketentuan Pasal 5 Perma No. 1 tahun 1999 yang memperkenalkan prosedur ‟permohonan‟ untuk pengujian peraturan dibawah undang-undang terhadap undang-undang yang mestinya hasil akhir dari pengujian tersebut adalah dengan kata ‟penetapan‟ atau perkara permohonan dimasukkan dalam perkara voluntair. Namun demikian, ternyata semua hasil pemeriksaan, dan penilaian atas pengujian peraturan dibawah undang-undang terhadap undang-undang Perma No. 1 tahun 1999 tetap menggunakan kata ‟putusan‟. Hal ini disebabkan bahwa perkara pengujian peraturan, tidaklah sama dengan perkara ‟voluntair‟ karena permohonan keberatan yang diajukan bukan untuk diri sendiri para pemohon, tetapi justeru untuk kepentingan umum, sehingga dalam perkara ini tetap terdapat 2 (dua) pihak yang berperkara. Putusan dalam pengujian peraturan dibawah undang-undang terhadap 57 . Lihat pasal 8 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 1999 Pemeriksaan perkara pengujian peraturan perundang-undangan pada prinsipnya dilakukan secara „judex factie‟, artinya Majelis Hakim Agung hanya memeriksa perkara sesuai yang diajukan dan tanpa menghadirkan pihak-pihak yang berperkara. Walaupun pemeriksaan perkara pengujian peraturan dibawah undang-undang terhadap undang-undang baik melalui gugatan maupun melalui permohonan yang dilakukan secara „judex factie‟ tidaklah mengurangi nilai keakuratan dan keadilan yang diminta oleh para pihak yang berperkara. Tetapi justeru lebih mengutamakan kehati-hatian, karena produk putusan tersebut tidak berdampak pada orang perorang, melainkan masyarakat secara luas. 58 Lihat pasal 8 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 1999. 26 undang-undang dibagi dalam 3 (tiga) jenis putusan yaitu;59 (1) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa gugatan itu beralasan, karena peraturan perundang-undangan dimaksud bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan tersebut. Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut sebagai tidak sah dan tidak berlaku untuk umum serta memerintahkan dengan segera pencabutannya kepada instansi yang bersangkutan. (2) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa gugatan itu tidak beralasan, Majelis Hakim Agung menolak gugatan tersebut. (3) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dijatuhkan setelah pihak tergugat didengar keterangannya. Demikian pula dengan perkara 'permohonan', dapat dilihat penjelasan pasal 10 ayat (1), (2), dan (3), yaitu: (1) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan keberatan itu beralasan, karena peraturan perundang-undangan dimaksud bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan keberatan tersebut. (2) Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimohonkan keberatan tersebut sebagai tidak sah dan tidak berlaku untuk umum serta memerintahkan dengan segera pencabutannya kepada instansi yang bersangkutan. (3) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan keberatan itu tidak beralasan, Majelis Hakim Agung menolak permohonan keberatan tersebut. Disamping putusan ‟mengabulkan‟, dan ‟menolak‟ juga ada putusan ‟tidak diterima‟ yakni jika berkas perkara tersebut tidak memenuhi syarat administratif. Dengan demikian, putusan yang diambil oleh Majelis Hakim Agung terhadap ‟gugatan‟ dan ‟permohonan‟ keberatan, sama-sama menggunakan kata ‟putusan‟ menjadikan perkara pengujian peraturan perundang-undangan pada perkara yang bersifat ‟contentieus‟, dan bukan perkara ‟voluntair‟ walaupun prosedurnya menggunakan ‟permohonan‟. 4. Pelaksanaan Putusan Pelaksanaan putusan sebagaimana yang diatur dalam Perma No. 1 Tahun 1993 dinyatakan bahwa apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat gugatan beralasan, maka gugatan dikabulkan dengan menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang digugat sebagai tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi. 59 Lihat Pasal 9 ayat (1), (2), (3), dan (4) dan Pasal 10 ayat (1), (2), (3), dan (4) Perma No. 1 Tahun 1999. 27 Pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI tersebut selanjutnya diserahkan kepada Instansi/pejabat yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan dimaksud.60 Ketentuan tersebut di atas memposisikan Mahkamah Agung sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh UUD 1945 sebagai pelaksana tertinggi kekuasaan kehakiman pada posisi yang lemah, karena putusannya tidak segera dapat mengikat, tetapi justeru tergantung kepada kemauan politik dari pembuat peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, ketentuan tersebut diubah melalui Perma No. 1 Tahun 1999, dimana pasal 12 ayat (1) dan (2) dan pasal 13 ayat (1) dan (2) menyatakan dengan tegas atas pelaksanaan putusan tersebut. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 12 Perma No. 1 tahun 1999 (1) Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya negara. (2) Dalam hal 90 (sembilan puluh hari) setelah putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada Tergugat, ternyata Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 13 Perma No. 1 tahun 1999 61 (1) Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya negara. (2) Dalam hal 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata Pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum. Ketentuan tersebut di atas memberikan dasar pijak yang kuat kepada Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam perkara pengujian peraturan perundang-undangan. Semua keputusan pengujian peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk diumumkan melalui Berita Negara, yang semula hal ini tidak diatur.62 Di samping itu, ditentukan batasan waktu 90 60 Lihat Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1993. Ketentuan ini merupakan pemberian sanksi atas pelaksaan putusan Mahkamah Agung kepada Pejabat atau instansi yang berkaitan dengan peraturan yang diputus oleh Mahkamah Agung, tetapi yang masih menjadi kendala adalah ketika yang bersangkutan yak instansi atau pejabatn administrasi negara tidak menjalankan putusan Mahkamah Agung untuk mencabut dan/atau mengubah ketentuan yangsudah dinyatakan oleh Mahkamah Agung tidak berlaku dan tidak mengikat secara umum. Masalah mendasar dalam kaitan ini adalah tidak adanya lembaga paksa seperti pada perkara pidana dan perdata, sehingga yang bersangkutan dapat menjalankan putusan Mahkamah Agung tersebut. 62 Pemuatan putusan majelis hakim dalam perkara pengujian peraturan perundang-undangan dalam Berita negara merupakan konsekuensi dari ketentuan Pasal 13 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 1999 agar dapat memaksa instansi yang bersangkutan untuk segera mencabut peraturan yang telah diputus oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 12 dan 13 Perma No. 1 tahun 1999 cukup maju dan mencerminkan betapa kuatnya hukum untuk memaksa subyek hukum untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum. Hal 61 28 (sembilan puluh) hari untuk mencabut peraturan perundang-undangan tersebut, dan jika tidak dicabut , maka dinyatakan tidak berlaku secara otomatis. Perubahan drastis ketentuan tentang hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan melalui Perma No. 1 Tahun 1999 atas Perma No. 1 Tahun 1993, memang sudah menjadi tuntutan sejarah. Perubahan dimaksud sebenarnya sejalan dengan perubahan sosial politik di Indonesia, akibat dari pernyataan berhenti Soeharto sebagai Presiden dan tuntutan reformasi termasuk didalamnya adalah reformasi hukum. Menurut penilaian Mahkamah Agung, Perma No. 1 Tahun 1993 sudah kurang memadai bahkan dianggap sebagai instrumen yang kurang mendukung terhadap reformasi hukum. Untuk itu, diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 199963 sebagai pengganti Perma No. 1 Tahun 1993. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 Tahun 1999 diterbitkan adalah untuk menampung aspirasi yang berkembang dalam masyarakat yang menuntut diadakannya reformasi hukum dalam rangka tegaknya supremasi hukum dan kemandirian badan peradilan sebagaimana yang diamanatkan Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.64 Perma No. 1 Tahun 1999 pada dasarnya hanya menyempurnakan Perma No. 1 Tahun 1993 yang berkehendak agar Mahkamah Agung bersikap lebih kreatif, di samping mengefektifkan dalam pelaksanaan fungsi dan kewenangan Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan perundang-undangan sebagaimana yang ditentukan. Secara substansial materi yang diatur dalam Perma No. 1 Tahun 1999 lebih progresif di banding dengan Perma No.1 Tahun 1993, yaitu diaturnya pelaksanaan putusan yang sebelumnya tidak diatur secara limitatif, tetapi secara teknis tidak terlalu jauh berbeda, dan yang membedakannya adalah pada pengaturan pelaksanaan putusan dan prosedur pengajuan ditambah dengan permohonan. Semula pelaksanaan putusan atas pengujian peraturan perundangundangan diserahkan kepada instansi atau pejabat yang bersangkutan. Tetapi dalam Perma No. 1 Tahun 1999 diberikan waktu limitatif yakni 90 hari setelah putusan dikirim kepada tergugat (instansi/pejabat), dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak juga dilaksanakan, maka demi hukum peraturan perundangundangan yang bersangkutan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Perbedaan pokok antara perma No. 1 Tahun 1993 dengan Perma No. 1 Tahun 1999, antara lain:65 ini juga tercermin komitmen terhadap penegakan negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum. 63 Peraturan MA No. 1 Tahun 1999 dikeluarkan tanggal 20 Mei 1999, saat Ketua MA dijabat oleh Sarwata. Peraturan ini memberikan alternatif dalam mengajukan perkara pengujian yakni melalui ‟permohonan‟, di samping ‟gugatan‟. 64 Lihat Konsideran dalam pertimbangan huruf c Perma No. 1 Tahun 1999. 65 Sri Soemantri Mertosoewignyo, Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Masalah Hukum Hak Uji Materiil, (Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI, 1999/2000), hal.2830. 29 1) 2) 3) 4) 5) Dalam Perma No. 1 Tahun 1993, tidak dimungkinkan pengajuan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan, tetapi hanya dapat diajukan dalam bentuk gugatan (Pasal 1 Perma No. 1 Tahun 1983). Tetapi dalam Perma No. 1 Tahun 1999 pengajuan permohonan pengujian peraturan perundangan dapat diajukan, di samping melalui cara mengajukan gugatan (Pasal [2] dan [5] Perma No. 1 Tahun 1999). Diktum putusan dalam Perma No. 1 Tahun 1993 hanya menyatakan peraturan perundang-undangan yang digugat tersebut 'sebagai tidak sah', karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tnggi. Sedangkan dalam Perma no. 1 Tahun 1999, putusannya lebih tegas yaitu apabila permohonan atau gugatan tersebut dengan 'Mahkamah Agung menyatakan bahwa peraturan perundangundangan yang digugat atau dimohonkan keberatan sebagai tidak sah dan tidak berlaku untuk umum serta memerintahkan dengan segera pencabutannya kepada instansi yang bersangkutan' (Pasal 9 dan 10 Perma No. 1 Tahun 1999). Dalam Perma No. 1 Tahun 1993 tidak diatur agar petikan putusan pengujian peraturan perundang-undangan dicantumkan dalam 'Berita Negara' dan dipublikasikan atas biaya negara. Ketentuan demikian diatur dalam Perma No. 1 Tahun 1999 ( Pasal 12 ayat [1]). Dalam Perma No. 1 Tahun 1993 tidak diatur batas waktu pengajuan gugatan, tetapi dalam Perma No. 1 Tahun 1999 hal tersebut diatur yaitu, terhadap semua peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum dikeluarkan Perma No. 1 Tahun 1999 hanya dapat digugat atau dimohonkan selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 1 Juni 2000. Dalam Perma No. 1 Tahun 1993, tidak diatur bagaimana kekuatan hukum suatu peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, apabila instansi yang bersangkutan tidak atau belum mencabutnya. Tetapi dalam Perma No. 1 Tahun 1999 diatur secara tegas, yaitu dalam tenggang waktu 90 hari setelah putusan Mahkamah Agung dikirim kepada tergugat atau pemohon, dan ternyata tidak dilaksanakan kewajibannya, maka demi hukum peraturan perundang-undangan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum lagi (Pasal 12 ayat [2]). Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor: 1 tahun 1993 dan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1999 yang membuka 2 (dua ) jalan tentang pengajuan pengujian peraturan perundang-undangan yaitu, melalui prosedur ‟gugatan‟ dan „permohonan keberatan‟ dimaksudkan sebagai upaya Mahkamah Agung untuk membuka pintu kepada masyarakat yang berkeinginan mengajukan pengujian terhadap peraturan dibawah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan undang-undang. Peraturan Mahkamah Agung merupakan peraturan untuk menjabarkan tugas yang diperintahkan oleh undang-undang dasar dan/atau undang-undang, dan produk hukum ini tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan karena sifatnya teknis dan internal. Walaupun demikian, Mahfudz menganggap bahwa Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1999, yang membuka pintu ‟permohonan 30 keberatan‟ merupakan mengadakan hal yang baru, dan hal ini dianggap menyimpang dari materi muatan undang-undang dasar dan undang-undang. Pemberian kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan kepada Mahkamah Agung, tidak dengan sendirinya kewenangan tersebut dapat dilaksanakan dan mendapat respons dari masyarakat. Hal ini disebabkan selain pengaturannya sangat ketat dan hampir tidak dapat dilaksanakan, juga kepercayaan masyarakat pada lembaga Mahkamah Agung juga tidak terlalu besar. Dua hal tersebut memberikan dampak terhadap penilaian yang kurang proporsional dari masyarakat kepada Mahkamah Agung, bahkan Mahkamah Agung dapat digolongkan pada posisi pinggiran. IV. Penutup Sebagai kontrol normatif, maka pengujian dapat dilakukan oleh lembaga pembuatnya sendiri atau juga dapat dilakukan oleh lembaga di luar lembaga pembuat peraturan tersebut. Apabila pengujian yang dilakukan oleh lembaga pembuatnya dapat disebut pengujian internal atau pengawasan internal, tetapi jika yang melakukan pengujian tersebut adalah lembaga di luar lembaga pembuatnya dapat disebut pengujian eksternal atau pengawasan eksternal. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa lembaga pembuat peraturan perundang-undangan dimungkinkan menguji produk hukumnya sendiri, dan apabila kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dilekatkan pada legislatif maka kontrol normatif pengujian tersebut lazim disebut legislativie review yang obyeknya adalah undang-undang dan undang-undang dasar dan produk hukum yang setara dengan itu. Apabila kewenangan pembentukan peraturan tersebut adalah eksekutif atau pemerintah yakni peraturan-peraturan sebagai pelaksanaan perintah undang-undang atau peraturan sebagai pelaksanaan fungsi dan tugas penyelenggaraan pemerintahan, maka kontrol normatif atau pengujian tersebut lazim disebut executive review. Tetapi jika kontrol normatif terhadap berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh eksekutif dilakukan oleh lembaga di luar eksekutif dalam hal ini oleh lembaga kekuasaan kehakiman, maka kontrol normatif atau pengujian tersebut lazim disebut judicial review. Kontrol normatif ini dimaksudkan untuk mencegah agar segala bentuk kegiatan pemerintah dalam menjalankan kegiatan pemerintahan tidak terjebak pada praktek otoriterian, sebab kecenderungan kearah otoriterian sangat terbuka. 31 DAFTAR PUSTAKA Abraham, Henry J. The Judicial Process - An Introductory of the Court of The United States, England, and France, Third Edition Revised and enlarged (London: Oxford University Press, 1975) Adler, John, dan Peter English, Judicial Review of the Execuitive, dalam 'Constitutional and Administrative Law' ( London: Macmillan Profesional Masters, 1989) Asshiddiqie, Jimly, Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, (Jakarta: Konstitusi press, 2005) _________________, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004) Attamimi, A. Hamid., Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara - Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I - Pelita IV, disertasi yang dipertahankan di hadapan Senat Guru Besar Universitas Indonesia tanggal 12 Desember 1990 di Universitas Indonesia Effendi, Paulus, Lotulung, Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap pemerintah, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993) Friedmann, W, Legal Theory, Fifth Edition(New York: Columbia University Press,1967) Kelsen, Hans, General Theory Theory of Law and State, (New York: Russell & Russell, 1945) _______________, Pure Theory of Law, (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1978), Kommers, Donald P.,„Cross-National Comparations of Cnstitutional Court Toward a Theory of Judicial Review, Paper - presented at the annual meeting of the American Political Science Association, (Los Angeles, Calif, September 11, 1970). Le Sueur, AP., dan JW Herberg, Introduction to the Grounds of Judicial Review, dalam 'Constitutional and Administrative Law, (London, British Library Cataloguing in Publication Data, 1995), hal. 204. Marzuki, M.Laica, Berjalan-jalan di Ranah Hukum, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 67 32 Manan, Bagir, Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-Undangan, Makalah disajikan pada Penataran Dosen dalam kegiatan Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung, 11 Nopember 1994, Martosoewignjo, Sri Soemantri, Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Masalah Hukum Hak Uji Materiil, (Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI, 1999/2000), Nawiasky, Hans, Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe, cet. kedua (Einsiedeln/Zurich/Koln: Benziger, 1948), hal.31 Nugaraha, Safri dkk, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2005), hal. 77. Raz, Joseph, The Concept of a Legal System, Oxford: Oxford Soedirjo, Mahkamah Agung - Uraian Singkat tentang Kedudukan, Susunan Kekuasaannya menurut UU No. 14 Tahun 985, (Jakarta: Media Sarana Press, 1987), Tanenhus, Joseph, Judicial Review, entri dalam " An International Encyclopedia of the Social Sciences", (Macmillan, 1968). Teeuw, A., Kamus Indonesia - Belanda (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal.260 dan 842 yang menjelaskan bahwa toetsing diartikan pengujian, toetsen diartikan menguji dan recht diartikan hak atau hukum, sehingga toetsingrecht dapat diartikan sebagai kewenangan untuk menguji atau untuk melakukan pengujian. Williams, Jerre S., “Constitutional Analysis in a Nutshell”, (St. Paul Minn: Weat Publishing co, 1979) 33