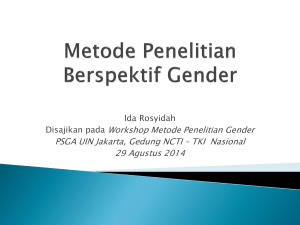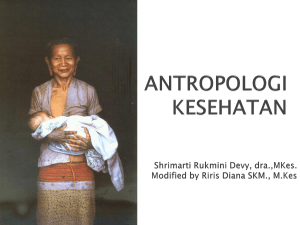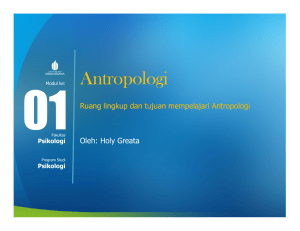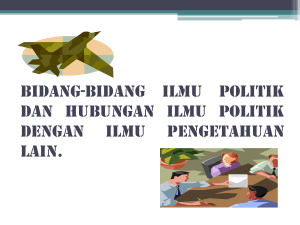Paradigma Baru bagi Pengkajian Masalah Wanita dan
advertisement

Paradigma Baru bagi Pengkajian Masalah Wanita dan Jender dalam Antropologi1 T.O. Ihromi (Univeritas Indonesia) Abstract In this article the author argues for the need to develop and use a new paradigm in examining the role of women. By considering the significant role women played in the recent economic crisis in Indonesia which has been neglected by various parties, including scholars, the author prefers strongly to use the paradigm ‘criticts’ in the studies about women. She explains further the difference between this paradigm and the ‘interpretive’ and positivism’ paradigms. The use of the new paradigm would enable the researcher to examine the relevant issues, carry out a participative approach, as well as change the disadvantaged situations and roles the women have. Pendahuluan Dalam penelitian-penelitian antropologi umum, wanita tentunya juga menjadi fokus kajian, namun, yang dipermasalahkan oleh para pemerhati masalah-masalah wanita dan jender adalah bagaimana penggambaran tentang wanita itu, dan bagaimana interpretasi peneliti mengenai peran wanita yang dikajinya. Mengutip hasil-hasil pengkajian terhadap wanita suku Aborigin Australia, Henrietta Moore (1998) menilai bahwa para antropolog pria menggambarkan wanita sebagai pencemar, secara ekonomis tidak penting, sedangkan antropolog wanita menggambarkannya sebagai orang-orang yang memainkan peranan sentral 1 Tulisan ini merupakan hasil penulisan ulang dari makalah yang disajikan dalam Sesi ‘Menjelang Abad ke-21: Teori dan Metodologi’ dalam Seminar Jubileum ke-30 Jurnal ANTROPOLOGI INDONESIA, ‘Memasuki Abad ke-21: Antropologi Indonesia Menghadapi Krisis Budaya Bangsa’, 6-8 Mei 1999, di Pusat Studi Jepang, Kampus Universitas Indonesia, Depok. 50 dalam ekonomi subsisten (Moore 1998:9-10). Penggambaran antropolog pria itu bersumber pada ‘bias’ yang melatarbelakangi visi mereka dan yang mewarnai analisis mereka. ‘Bias’ itu adalah anggapan bahwa pria dalam masyarakat yang dikaji memiliki informasi yang penting dan bukanlah wanita. Bias yang lain melekat pada masyarakat yang diteliti. Terdapat anggapan yang umum bahwa wanita adalah subordinat bagi pria, dan inilah yang langsung diterima oleh peneliti pria. ‘Antropologi Wanita’ muncul dalam rangka mengadakan koreksi terhadap pendekatan yang bias pria itu. Walaupun para penganutnya berjasa dalam memperkaya karya-karya antropologi yang mengoreksi pendekatan ‘bias’ pria, sumbangansumbangan yang berarti dalam bidang teori barulah terjadi melalui antropologi feminis. Salah satu unsur dalam metodologi feminis adalah keberpihakan peneliti terhadap sasaran penelitiannya. Penelitian Jutta Berninghaussen ANTROPOLOGI INDONESIA 60, 1999 dan Birgit Kerstan (1992) di Jawa Tengah merupakan contoh penelitian yang menggunakan metodologi feminis. Penelitian tersebut bertitik tolak dari sejumlah postulat seperti: sikap yang secara sadar mengadakan negasi terhadap netralitas, solidaritas kepada wanita dan identifikasi parsial dengan para wanita yang dikaji. Selain untuk mencapai sesuatu, seseorang harus memanfaatkan hasilhasil kajiannya untuk membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi wanita. Peneliti harus membantu mencapai perubahan dan perlu berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan emansipatoris. Krisis ekonomi dan peranan ekonomi wanita Krisis ekonomi mulai melanda Indonesia pada bulan Agustus 1997. Mula-mula krisis ekonomi itu dipandang sebagai krisis keuangan saja, akibat dari peristiwa-peristiwa di berbagai negara Asia. Pendapat-pendapat optimis mengemukakan bahwa krisis ekonomi tersebut akan teratasi dalam waktu cepat berhubung kondisi fundamental ekonomi Indonesia lebih baik keadaannya dibandingkan dengan negara lain. Namun, proses pemburukan yang terjadi di segala bidang, menyadarkan bangsa Indonesia bahwa krisis yang berlangsung bersumber pada kegiatan-kegiatan ekonomi yang tidak efisien, manajemen yang keliru (mismanagement) dan high-cost economy . Para birokrat menjadi mitra dari para pengusaha besar dan para pejabat pemerintahan cenderung untuk mengambil kesempatan-kesempatan menguntungkan diri sendiri, ketika warga masyarakat memerlukan pelayanan. Praktekpraktek korupsi, kolusi, nepotisme merajalela (Wilopo dan Adioetomo 1999:2). Jelaslah bahwa kondisi ekonomi yang terus menerus memburuk itu dan yang telah menimbulkan pembengkakan dari jumlah penduduk miskin di Indonesia bersumber pada krisis moral, krisis ANTROPOLOGI INDONESIA 60, 1999 budaya. Berbagai kajian dan pengamatan mengungkapkan bahwa wanita termasuk kategori penduduk yang paling terkena oleh dampak krisis ekonomi (Gardiner 1999:130). Namun, wanita tidak dapat membiarkan diri menganggur mengingat kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi. Karena itu, mereka melakukan apa saja yang masih dapat menghasilkan sesuatu untuk menutupi keperluan anggota-anggota rumah tangga (Gardiner 1999:133). Peranan ekonomi dari wanita inilah yang tidak diakui setepatnya dalam ilmu-ilmu sosial yang mengkaji ekonomi rumah tangga. Karena itu, perencanaan ekonomi, alokasi dana JPS misalnya, tidak menyentuh ibu-ibu rumah tangga yang dalam kenyataan begitu besar peranannya dalam penyediaan bahan-bahan pemenuhan kebutuhan vital keluarga, yang memang sangat terlanda oleh krisis yang multidimensional itu. Penggunaan paradigma baru dalam meneliti peranan ekonomi wanita, seperti yang diadvokasikan oleh antropologi feminis akan memungkinkan pengungkapan informasi, data mengenai peranan wanita dan pengalamanpengalamannya. Dengan keberpihakan pada masalah-masalah mereka, peneliti perlu merumuskan upaya-upaya yang dapat memecahkan masalah mereka. Terabaikannya peranan produktif wanita Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Inilah salah satu aturan dalam Undang-undang Perkawinan (Pasal 31 (3)). Aturan lain yang masih hendak saya kutip adalah: suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya ada pula pasal 34 (1): Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga 50 sebaik-baiknya. Kutipan-kutipan tadi mengungkapkan bahwa dalam hukum formal, struktur dalam rumah tangga bersifat asimetris, yaitu bapaklah yang menjadi pemimpin. Dia bergerak di luar rumah tangga untuk mencari nafkah, sedangkan isteri adalah ibu rumah tangga yang tugasnya mengurus rumah tangga. Istri adalah orang yang tempatnya di rumah, tidak dimaksudkan bergerak di luar rumah. Pembagian kerja yang berdasarkan jenis kelamin ini merupakan gagasan budaya yang diabsahkan oleh hukum. Dalam kenyataannya, wanita—terutama wanita dari lapisan ekonomi paling bawah—’tidak bisa bermewah diri dan berada di dalam rumah saja’. Seorang istri akan selalu menggali berbagai kesempatan, sehingga akan dapat menghasil-kan sesuatu. Namun, pekerjaan-pekerjaan produktif dari wanita itu dianggap sebagai bagian dari pekerjaan rumah saja. Dalam penyusunan statistik ekonomi, berbagai kegiatan wanita yang bersifat produktif itu tidak dianggap perlu dicakup dalam angka-angka yang menggambarkan produktivitas dalam suatu masyarakat. Pengingkaran terhadap peranan ekonomi wanita tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia. Charlton, seperti yang dikutip dalam Moore (1988:43), mengemukakan bahwa setengah dari kaum wanita di seluruh dunia hidup dan bertani di negara-negara sedang berkembang, dan menghasilkan 40-80% dari seluruh produksi hasil pertumbuhan ekonomi, namun hal itu tidak diakui. Gagasan-gagasan budaya tentang peranan yang wajar dari wanita, tentang hubungan antara pria dan wanita, atau apa yang dikembangkan dalam kajian tentang wanita (women’s studies), disebut hubungan jender. Konsep pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin, tidaklah dipertanyakan oleh warga masyarakat pada umumnya. Gagasan-gagasan itu menjadi pengarah bagi tindakan-tindakan mereka, misalnya dalam pendidikan anak perempuan. 52 Gagasan-gagasan itu memberi petunjukpetunjuk tentang gambaran ideal tentang apa yang menjadi model kepribadian anak yang ingin mereka ‘cetak’ dari para anak asuh. Pada umumnya, para anak wanita akan terbentuk menjadi makhluk-makhluk feminin, halus dsb., atau terjadi konstruksi sosial yang menghasilkan wanita yang aspirasinya berbeda dari pria. Secara statistik dapat pula diamati salah satu akibatnya, yaitu tingkat pendidikan wanita yang umumnya lebih rendah daripada pria. Peran-peran seks juga terbentuk berdasarkan gagasan-gagasan tersebut. Wanita tahu dan menghayati secara penuh bahwa peran reproduktif mereka adalah peran yang harus diutamakan. Ketika wanita menjadi isteri dalam rumah tangga, tugas-tugas reproduktif, melahirkan, memberi pelajaran kepada anak, merupakan tanggung jawabnya. Tugas-tugas itu menyita waktu dan perhatiannya secara penuh. Kenyataannya, tugas mengurus rumah tangga itu—terutama dalam rumah tangga miskin— juga dibebani dengan tugas untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan anggota keluarga. Terlalu ‘mewah’ bila wanita tidak turut aktif mengupayakan mencari ‘nafkah tambahan’. Peran ganda inilah yang menyebabkan curahan waktu isteri lebih panjang daripada curahan waktu suami untuk pelaksanaan tugas-tugas mereka. Kajian Wanita: peduli isu-isu wanita dan paradigma baru Para wanita di dunia kampus menyadari berbagai bentuk perlakuan yang menomorduakan mereka dibandingkan dengan laki-laki. Tetapi, saat mereka ingin memperoleh gambaran mengenai tempat mereka dalam dunia yang nyata, berbagai perlakuan yang diskriminatif, secara implisit maupun eksplisit dalam masyarakat, serta memperoleh jawabanjawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang ANTROPOLOGI INDONESIA 60, 1999 sumber dan perlakuan berbagai ketimpangan tersebut, mereka menghadapi kenyataan bahwa isu-isu tersebut tidak digubris dalam ilmu-ilmu yang disajikan di perguruan tinggi. Terutama bila mereka hendak mencari pemecahan masalah-masalah tersebut, upaya demikian dianggap tidak ilmiah. Kepedulian pada masalah wanita ini, diawali dengan adanya pertemuan-pertemuan para peminat yang datang dari berbagai disiplin ilmu, lalu terjalin komunikasi antarmereka. Melalui komunikasi antar peminat di berbagai kampus dan lembaga-lembaga penelitian, muncul suatu pengkajian yang memusatkan perhatiannya pada isu-isu wanita. Isu-isu semacam itu dianggap tidak bermakna untuk kajian ilmu sosial, termasuk antropologi umum. Para peminat masalah wanita menyadari bahwa pengalaman-pengalamann wanita dan hubungannya dengan fenomena lain, perlu dikaji. Dengan demikian, upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan wanita dapat dilakukan. Berkaitan dengan tujuan-tujuan—yang oleh para peminat kajian dianggap sangat bermakna—maka dengan pendekatan kritis, mereka mempertanyakan pendekatanpendekatan, yang dinilai bersifat baku dalam berbagai disiplin, termasuk antropologi. Penelitian Jutta Berninghausen seperti yang telah dikemukakan sebelumnya—yang memperhatikan negasi terhadap netralitas dan solidaritas terhadap wanita—secara sengaja diajukan sebagai alternatif terhadap penelitian bidang lmu sosial umum yang secara baku mensyaratkan pengambilan jarak oleh peneliti dari apa yang hendak dikaji. Keberpihakan pada yang dikaji dan kepekaan terhadap masalah yang dialami memungkinkan peneliti memahami akar permasalahan yang hendak dipelajari. Pengalaman wanita, dalam pendekatan yang ANTROPOLOGI INDONESIA 60, 1999 berperspektif feminis, menjadi hal yang sangat penting dan diakui sebagai sesuatu yang absah, agar peneliti mampu merumuskan masalah yang sangat perlu dikaji. Peneliti dituntut untuk tidak berhenti pada tahap penyajian laporan, tetapi juga melakukan pengkajian pencerahan mengenai pemahaman isu-isu wanita. Hal itu dapat mendorongnya untuk merumuskan upaya-upaya untuk pemecahan masalah wanita. Peneliti harus memberi sumbangan ke arah pembebasan wanita dari masalah-masalahnya. Pengalaman wanita itu sangat sentral sifatnya, baik dalam seluruh proses pengkajian yang berperspektif feminis, maupun pada tahap pencarian upaya pemecahan. Karena itu, paradigma feministik mengembangkan pendekatan partisipatif yang menekankan bahwa pada semua tahap penelitian, keturutsertaan orang yang dikaji hakiki sifatnya, sehingga peneliti dan yang diteliti akan punya hubungan kemitraan. Hal lain yang membuat kajian wanita itu mampu memperoleh pemahaman tentang masalah-masalah secara komprehensif adalah kerjasama antar disiplin. Dalam contoh yang dibahas, isu pekerjaan wanitalah yang dikemukakan. Isu-isu lain yang dalam waktu cukup lama tidak dianggap bermakna di kalangan pemerhati ilmu sosial umum, seperti hubungan jender yang ditandai oleh kekuasaan pria; penyalahgunaan dari kedudukan oleh suami sehingga menimbulkan tindakan-tindakan kekerasan dalam keluarga; pranata-pranata ekonomi dalam masyarakat yang mengandung unsur kendala bagi pengembangan peranan ekonomi dari wanita, dapat terangkat menjadi topik kajian ilmiah. Kita pun akan menyaksikan pengembangan kepustakaan yang semakin kaya. Tiga paradigma utama Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai perobahan paradigma yang telah dikemukakan dalam butir tentang kajian wanita, 52 akan dijelaskan pemikiran-pemikiran yang melatarbelakangi hal tersebut. Mengikuti seorang ahli metodologi penelitian bernama Sarantakos, saya hendak memberi patokan mengenai sejumlah istilah yang akan digunakan dalam uraian singkat ini, yaitu paradigma, metodologi dan metode. Perlu diingat bahwa penelitian ilmu sosial merupakan suatu proses yang kompleks dan didasarkan pada pandangan-pandangan teoritis yang sangat beragam, atau dalam perkataan Sarantakos, berlangsung sebagai proses yang pluralistik (Sarantakos 1993:30). Karena itu, istilahistilah seperti paradigma juga diartikan berbeda oleh berbagai penulis. Dalam tulisan ini akan saya gunakan pendapat Sarantakos sebagai patokan. Paradigma, menurut Sarantokos (mengutip Patton 1990:37) adalah suatu perangkat proposisi yang memberi penjelasan mengenai bagaimanakah dunia dipersepsikan, suatu cara bagaimana dunia yang kompleks itu dipilah-pilah. Paradigma itu mengemukakan kepada para peneliti dan ilmuwan sosial pada umumnya, apakah yang penting, apakah yang sahih (legitimate), dan apa yang ‘masuk akal’. Suatu metodologi adalah suatu model yang mencakup prinsip-prinsip teoritis dan kerangka pemikiran yang memuat pedoman mengenai bagaimana penelitian dilakukan dalam konteks suatu paradigma. Dengan perkataan lain, suatu metodologi menerjemah-kan suatu paradigma dalam bahasa penelitian, dan menunjukkan bagaimana keberadaan dunia nyata dapat dijelaskan, bagaimana dunia dapat ditangani, dapat didekati atau dipelajari. Metode adalah instrumen yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan bukti-bukti empirik (Sarantakos 1993:30). Menurut Sarantakos, walaupun tidak terdapat kesepakatan antara para ilmuwan sosial mengenai aliran-aliran pemikiran yang mana yang dapat dianggap sebagai suatu paradigma, (misalnya ada yang beranggapan bahwa 54 phenomenologi, Marxisme, feminisme hermeneutika, feminisme adalah paradigma), namun kebanyakan ilmuwan sosial sepakat bahwa dewasa ini ada tiga paradigma utama yang digunakan sebagai pedoman dalam teori dan penelitian sosial (Sarantakos 1993:33).2 Ketiga paradigma itu adalah paradigma positivistik, interpretif dan kritis. Positivisme merupakan paradigma tertua dalam ilmu sosial. Sampai sekarang pun kebanyakan ilmuwan sosial masih mendasarkan penelitiannya pada paradigma ini. Suatu hal yang perlu diketahui adalah bagaimana pandangan tentang kenyataan dalam paradigmaparadigma itu. Dalam pandangan positivistik, realitas adalah semua hal yang dapat diamati melalui indera. Kenyataan dianggap sebagai sesuatu yang berada ‘di luar sana’ dan berada di situ tanpa ditentukan, atau terlepas dari kesadaran manusia. Kenyataan itu bersifat objektif, keberadaannya bertumpu pada keteraturan, dan dikuasai oleh hukum-hukum yang alamiah, yang tidak dapat diubah, dan dapat diwujudkan melalui pengalaman. Semua anggota masyarakat mendefinisikan kenyataan dalam pengertian-pengertian yang sama, karena mereka semuanya menganut makna atau pengertian-pengertian yang sama. Persepsi tentang kenyataan paradigma interpretif berbeda dari positivistik. Dalam paradigma interpretif ini, kenyataan tidaklah berada di ‘luar sana’, tetapi dalam pikiran manusia. Kenyataan itu dialami secara internal, dikonstruksi secara sosial melalui interaksi, dan diinterpretasikan oleh para pelaku atau aktoraktor dan didasarkan pada definisi yang diberikan pada hal tersebut. Realitas adalah subyektif, bukan obyektif. Kenyataan adalah apa yang dilihat orang sebagai realitas (Hughes dalam Sarantakos 1993:53). 2 Ada yang beranggapan bahwa fenomenologi, marxisme, feminisme hermeunetika dan feminisme adalah paradigma. ANTROPOLOGI INDONESIA 60, 1999 Dalam paradigma kritis, kenyataan dipersepsikan secara berbeda. Kenyataan bukanlah hasil kreasi alam, melainkan kreasi manusia, yaitu oleh manusia yang berkuasa. Mereka yang berkuasa itu memanipulasi orangorang lain, mengkondisikan mereka, ‘mencuciotak’ mereka, agar melihat hal-hal yang ada, dan memberi interpretasi mengenai hal-hal itu menurut kehendak mereka. Lebih jauh lagi, kenyataan itu tidaklah berada dalam keteraturan, tetapi berada dalam konflik, ketegangan dan saling bertentangan, yang menghasilkan suatu dunia yang secara terus-menerus berubah. Para penganut paradigma ini juga membedakan antara penampakan (appearance ) dan kenyataan. Apa yang tampak bukanlah kenyataan, karena yang sering terjadi, yang tampak itu, tidak mencerminkan konflik, ketegangan-ketegangan serta kontradiksikontradiksi yang nyata-nyata ada dalam masyarakat. Dasar dari hal-hal yang tampak itu adalah ilusi dan distorsi. Selanjutnya, ketiga paradigma ini juga mengandung persepsi yang berbeda mengenai manusia. Untuk para penganut positivisme, manusia adalah makhluk rasional dan manusia dikuasai oleh hukum-hukum sosial. Perilaku mereka dapat diketahui melalui pengamatan, dan dikuasai oleh hukum eksternal yang menghasilkan hal yang sama, artinya penyebab yang sama menghasilkan konsekuensi yang sama. Dalam perspektif interpretif, manusia mempunyai kedudukan yang sentral. Kenyataan dan dunia sosial diciptakan oleh manusia melalui sistem makna yang mereka berikan pada kejadian-kejadian. Kebanyakan penganut perspektif ini beranggapan bahwa tidak ada hukum-hukum yang memiliki watak membatasi. Namun, pola-pola dan keteraturanketeraturan timbul juga sebagai hasil dari konvensi-konvensi sosial yang terjadi melalui interaksi. Termasuk tugas dari ilmu sosial yang ANTROPOLOGI INDONESIA 60, 1999 interpretif untuk menemukan sistem-sistem makna yang digunakan oleh para pelaku untuk memperoleh makna dari dunia mereka (Sarantakos 1993:35). Dalam pandangan paradigma kritis, manusia mempunyai potensi untuk bersifat kreatif dan menyesuaikan diri. Namun, mereka dibatasi dan ditindas oleh faktor-faktor sosial dan kondisi-kondisi sosial, dan oleh sesamanya yang meyakinkan mereka bahwa nasibnya adalah tepat dan dapat diterima. Kepercayaan terhadap ilusi demikian menghasilkan kesadaran yang palsu dan menjadi kendala bagi perwujudan sepenuhnya dari potensi-potensi mereka (Sarantakos 1993:36). Bagaimanakah ilmu pengetahuan dipersepsikan dalam tiga paradigma ini? Dalam perspektif positivistik, ilmu pengetahuan didasarkan pada aturan-aturan dan prosedurprosedur yang ketat, dan sangat berbeda dari spekulasi dan akal sehat (common sense). Sebenarnya, ilmu tidak cocok untuk mempelajari kenyataan sosial, karena kenyataan itu mengandung bias, tidak sistematis dan secara logis tidak konsisten. Sifat yang kedua dari ilmu pengetahuan adalah deduktif, yaitu bertolak dari hal yang umum abstrak, lalu beranjak ke yang spesifik dan konkrit. Sifatnya yang ketiga, nomotetis, didasarkan pada hukum-hukum universal yang kausal yang digunakan untuk menjelaskan kejadiankejadian sosial yang konkrit, dan hubunganhubungan sosial. Sifat yang keempat, mengandalkan pengetahuan yang diperoleh melalui indra, sumber-sumber lain yang tidak dapat diandalkan. Sifat yang terakhir adalah bahwa ilmu pengetahuan memisahkan fakta dari nilai. Ilmu pengetahuan bersifat bebas-nilai. Dalam paradigma interpretif, ilmu pengetahuan dipersepsikan secara sangat berbeda. Pertamatama dikemukakan bahwa bias dari penjelasan mengenai kehidupan sosial dan kejadian sosial bukanlah ilmu pengetahuan menurut versi positivistik, melainkan akal sehat (common 54 sense), karena di dalamnya terdapat maknamakna yang digunakan manusia untuk memberi arti bagi kehidupannya. Kedua, pendekatannya adalah induktif, yaitu beranjak dari yang spesifik ke yang umum, dan dari yang konkrit ke yang abstrak. Ilmu disebut bersifat ideografis dan bukan nomotetis. Ilmu pengetahuan itu menyajikan kenyataan secara simbolik dalam bentuk deskriptif. Pengetahuan tidaklah hanya dihasilkan berdasarkan apa yang diamati melalui indra. Memahami makna dan memberi interpretasi mengenai hal yang diamati dianggap lebih penting. Terakhir disebutkan bahwa ilmu pengetahuan tidaklah bebas-nilai. Sifat netral nilai menurut perspektif ini tidak diperlukan dan juga tidak mungkin terwujud. Pandangan mengenai ilmu pengetahuan dalam pendekatan kritis berada di antara posisi positivisme dan perspektif interpretif. Menurut para penganutnya, para aktor dihadapkan pada kondisi sosial-ekonomi yang memberi bentuk tertentu pada kehidupan mereka. Namun, para aktor itu mampu juga untuk memberi makna tertentu pada dunia mereka, dan sebagai respons bertindak untuk mengubah kehidupannya. Manusia dilihat sebagai aktor yang dapat menciptakan tujuan hidupnya, misalnya melalui perjuangan melawan ilusi, serta strukturstruktur yang mengungkungnya. Ilmu pengetahuan pun tidaklah bebas-nilai. Ilmu pengetahuan yang kritis adalah ilmu yang melibatkan diri, artinya mengambil peranan secara aktif, baik penelitinya, maupun pakar teorinya. Para peneliti tidak meneliti kenyataan, tetapi juga bertindak sebagai respons terhadap kenyataan (Sarantakos 1993:36-37). Sesuai dengan sifat-sifat ketiga paradigma tersebut, apakah tujuan dari penelitian sosial dalam ketiganya? Di kalangan para pengikut positivisme, penelitian sosial bersifat instrumental. Penelitian sosial adalah alat untuk mengkaji peristiwa-peristiwa sosial, dan mengkaji 56 hubungan antara peristiwa-peristiwa. Berdasarkan pengertian mengenai hubunganhubungan tersebut, dapat ditemukan hukumhukum umum dan penjelasan-penjelasan. Halhal itu didokumen-tasikan. Pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa sosial memungkinkan dibuatnya prediksi mengenai kejadian di masa datang. Dalam pandangan interpretif, penelitian sosial tidak memiliki nilai instrumental langsung. Melalui penelitian, orang terbantu dalam upayanya untuk memberi interpretasi mengenai alasan-alasan para aktor sosial untuk bertindak, memahami alasanalasan mereka untuk bertindak, memahami bagaimana mereka mengonstruksikan kehidupannya dan makna yang mereka berikan terhadapnya, serta untuk memahami konteks sosial dari tindakan sosial. Yang dipentingkan di sini bukanlah tindakan-tindakan sosial yang teramati, melainkan makna subyektif mengenai tindakan-tindakan sosial tersebut. Penelitian sosial dalam paradigma kritis harus memungkinkan peneliti untuk menjadi mampu ‘menangkap’ apakah yang ada pada akar masalah, dan mengungkapkan hubunganhubungan yang sebenarnya ada; untuk membongkar mitos-mitos dan ilusi; untuk menunjukkan kepada khalayak bagaimanakah dunia itu seharusnya; bagaimanakah dapat mewujudkan tujuan-tujuan sosial atau secara umum, bagaimana dapat mengubah dunia ini. Sarantakos mengutip kalimat-kalimat seorang pakar bernama Fay, sebagai berikut: ‘Ilmu sosial yang kritis menjelaskan sifat dari tatanan sosial, sehingga akan menjadi katalisator yang mengarahkan kepada transformasi tatanan sosial tersebut (Fay 1987:27 dalam Sarantakos 1993:37).’ Sampai tahun 1960 ilmu sosial masih didominasi oleh paradigma positivistik dan malahan sebenarnya secara umum, penelitipeneliti sosial masih berpegang teguh pada dalil-dalil positivistik tersebut. Namun, selama ANTROPOLOGI INDONESIA 60, 1999 lebih dari seperempat abad telah timbul tantangan-tantangan terhadap dominasi dari pemikiran positivistik yang diterapkan secara ketat terhadap fenomena sosial. Timbullah periode pasca empirik (Nielsen 1990:7). Tantangan utama datang dari kalangan pemikir yang ditandai oleh tradisi hermeneutik atau interpretif dan para pemikir aliran kritis. Yang paling ditantang adalah tuntutan terhadap peneliti untuk bersikap netral, serta sifat objektif dari dunia kenyataan. Kalau kita membaca buku-buku tentang metodologi penelitian sosial, akan terlihat bahwa dalam pendekatan positivistik atau naturalistik sangat ditekankan bahwa peneliti harus menjauhkan diri dari sikap-sikap keberpihakan pada para anggota masyarakat yang kehidupannya dikaji. Satu asumsi yang mendasar adalah pemisahan di antara peneliti yang subyektif dari realitas yang obyektif. Peneliti yang subyektif tidak diperkenan-kan untuk mencemari kebenaran yang obyektif (Nielsen 1990:4). Peneliti feminis: memilih pendekatan kritis Kalau kita pelajari latar belakang dari timbulnya gerakan feminisme, maka dapat disimpulkan bahwa pemikiran inti dari para penganut feminisme adalah pengakuan bahwa wanita mengalami ketidakadilan sosial karena mereka wanita. Wanita mengalami berbagai bentuk perlakuan diskriminatif di semua bidang kehidupan. Para feminis berketetapan hati untuk mengupayakan agar ketimpanganketimpangan tersebut berakhir, dan terhapuskan. Penelitian sosial yang bertitik tolak dari paradigma positivistik tidak akan dapat memuaskan mereka, bila mereka mengharapkan bantuan dalam mengungkapkan informasi tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh wanita. Terutama bila diharapkan analisis yang dapat mengungkapkan sebab-sebab ketidak- ANTROPOLOGI INDONESIA 60, 1999 adilan itu, serta bagaimana menemukan upaya pemecahan agar dapat menghasilkan keadilan jender. Peneliti positivistik melukiskan hasil pengamatannya, peneliti feminis berpihak pada wanita yang didiskriminasi. Peneliti feminis menggabungkan diri pada aliran yang menantang paradigma positivistik yang telah berkuasa sekian lama, dan yang masih berkuasa itu. Dalam memandang realitas atau kenyataan, misalnya, kaum feminis bersama kubu kritis mengritik pandangan bahwa realitas memiliki struktur yang obyektif. Mereka beranggapan bahwa hal-hal yang tampak, dalam banyak hal, tidak mencerminkan apa yang sebenarnya ada, yaitu ketegangan-ketegangan dan konflik. Melalui kajian yang dilakukan, hendak diekspos atau diungkapkan keadaan yang sebenarnya. Mitos-mitos dan ilusi harus dimunculkan ke permukaan. Dalam pandangan mereka, kenyataan didominasi oleh pandanganpandangan pria dan oleh kepentingan pria. Kepentingan-kepentingan itu bertentangan dengan kepentingan wanita (Sarantakos 1992:35). Jika manusia dalam paradigma positivistik dipersepsikan sebagai orang yang digerakkan oleh hukum-hukum sosial, dan tidak memiliki kemauan bebas, para peneliti feminis mengikuti kubu kritis dalam pandangannya, yaitu bahwa manusia mempunyai potensi untuk memiliki kreativitas. Ciri-ciri dari penelitian dengan perspektif feminis itu akan dijelaskan dengan mengacu pada penelitian seperti yang telah dilakukan oleh Jutta Berninghausen dengan Birgit Kerstan. Pemilihan topik kajian mereka saja telah menunjukkan keberpihakannya pada wanita. Mereka bertitik tolak dari kenyataan yang telah diamati, yaitu bahwa wanita di daerah pedesaan Jawa sejak masa-masa lalu bekerja giat untuk menyumbangkan penghasilannya pada ekonomi rumah tangga. Namun, yang menjadi pertanyaan mereka adalah: apakah 56 dengan adanya sumbangan ekonomi tersebut dari kaum wanita, secara otomatis meningkatkan kedudukan sosial mereka? Apakah wanita tersebut mempunyai kekuasaan dalam rumah tangga mereka, dan bagaimana pula kedudukan mereka dalam komunitas setempat? Topik kajian ini tidak akan mendorong peneliti untuk pergi jauh ke daerah yang asing baginya, bila dia mempunyai sikap yang netral terhadap hubungan pria wanita. Dalam penjelasan mengenai postulat sentral yang mereka terapkan, kedua peneliti mengemukakan bahwa dengan sadar mereka mengabaikan sikap netral. Mereka bertitik tolak dari sikap solider dengan wanita yang dikaji. Semua wanita, menurut mereka, termasuk suatu kategori politik yang terpengaruh oleh struktur patriarkhis. Selanjutnya mereka mengatakan, hal itu tidak berarti bahwa peneliti selalu harus menyetujui hal-hal yang menjadi sikap dan pendirian dari wanita yang dikajinya, atau bahwa peneliti memiliki hubunganhubungan pribadi dengan mereka. Pada umumnya, kondisi hidup dan bentuk-bentuk persepsi antara peneliti dan yang dikaji berbeda, sehingga hal-hal demikian tidak tercapai. Lebih jauh peneliti juga mengemukakan bahwa sikap tidak netral yang dilakukan secara sadar itu bukan saja didasarkan pada tergolongnya mereka dalam kategori jender yang sama-sama ditindas, serta fakta bahwa struktur-struktur secara jender bersifat diskriminatif yang menimbulkan akibat pada mereka sebagai wanita, melainkan dapat difahami pula sebagai ‘kesadaran kelas’ berbasiskan jender. Lebih lanjut kedua peneliti menjelaskan bahwa dalam Kajian Wanita yang seyogianya dilakukan adalah mengungkapkan dan menjelaskan struktur-struktur yang mendominasi, sehingga dapat mengakhiri diskriminasi yang sistematik terhadap wanita. Karena itu, tidak terelakkan bahwa kajian 58 wanita, oleh wanita, untuk wanita atau penelitian feminis akan memiliki corak politik dan berpihak pada wanita. Penelitian yang dibicarakan ini berlangsung di Gentuk suatu daerah permukiman dekat Klaten, dengan penduduk yang terdiri dari 60 keluarga. Suatu LSM, yaitu LP3ES mempunyai program-program pengembangan wanita di situ, tempat para wanita dibimbing menjadi peserta dalam kelompok-kelompok wanita yang melakukan kegiatan simpan-pinjam. Para wanita itu juga dibantu, sehingga kegiatankegiatan produktivitas mereka berkembang. Jelaslah bahwa yang dikaji adalah masalah wanita. Dalam penyusunan desain penelitian, pedoman-pedoman yang telah berkembang dalam paradigma positivistik juga tidak ‘mengikat mereka’. Peneliti memilih untuk menggunakan pendekatan studi kasus. Di samping itu, mereka juga menggunakan berbagai metode penelitian yang semuanya diperhitungkan sebagai metode atau teknik untuk memungkinkan dipahaminya perempuan dan permasalahannya (Sadli dan Porter 1999:45). Suatu hal yang rupanya sangat membantu para peneliti dalam membina rapport dengan penduduk setempat adalah identifikasi oleh penduduk pada kedua peneliti sebagai ‘Mama Max’ dan ‘Mama Lola’. Mereka juga dikenal sebagai para wanita yang ingin menceriterakan kehidupan wanita Jawa di Gentuk pada para wanita Jerman. Terdapat suatu postulat yang oleh para peneliti ini dianggap harus direvisi, yaitu yang berkaitan dengan postulat yang telah berkembang di kalangan para peneliti Feminis: ‘Untuk mencapai sesuatu, seseorang harus mengubah keadaan, harus berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan emansipatoris’. Menurut para peneliti, dalam penelitian di mana peneliti juga mengadakan kajian terhadap masyarakat dan kebudayaannya sendiri, hal ANTROPOLOGI INDONESIA 60, 1999 semacam itu acapkali dilakukan, karena adanya perbedaan-perbedaan di antara para peneliti dan mereka yang dikaji. Perbedaan-perbedaan itu dapat berupa perbedaan dalam identitas dan dalam minat, sehingga sukar untuk menyepakati kegiatan-kegiatan bersama. Dalam situasi yang dihadapi oleh kedua peneliti, keadaannya lebih sulit lagi. Peneliti takut bila usul mereka untuk mengadakan perubahan yang didasarkan pada anggapan-anggapan mereka yang didasarkan pada nilai-nilai yang mereka anut, akan mengarah pada hubungan subordinatif, diterima dan ditelan saja oleh wanita setempat tanpa memikirkannya. Ketika para peneliti membicarakan dengan para pembina LP3ES dan para pemimpin wanita setempat bahwa sangat baik untuk mengadakan penyadaran melalui diskusi terbuka tentang hal-hal yang terjadi, seperti perlakuan-perlakuan suami yang menyeleweng dalam bidang seksual, dan bertitik tolak dari contoh-contoh konkrit demikian menjadikan para wanita lebih sadar tentang struktur sosial yang patriarkhis itu (wanita menerima saja bila memperoleh perlakuan-perlakuan seperti itu), maka para pemimpin wanita tidak menyetujuinya. Membicarakan hal-hal yang demikian secara terbuka di muka umum, tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam kebudayaan Jawa. Mengingat bahwa mereka yang mengalami ketidakadilan dari struktur patriarkhis demikian tidak mempertanyakan kondisi-kondisi yang menurut peneliti harus dikecam, tidak mendorong kedua peneliti untuk menyampaikan lagi kritikankritikan peneliti secara terbuka, serta saran-saran untuk mengadakan perubahan. Beberapa penemuan dari Jutta Berninghausen dan Brigit Kerstan dapat disimak sebagai berikut : Wanita menyumbang secara sangat bermakna pada penghasilan keluarga. Di samping melaksanakan semua tugas-tugasnya sebagai ibu rumah tangga, para wanita di Gentuk ratarata menghasilkan 42 % dari pendapatan rumah ANTROPOLOGI INDONESIA 60, 1999 tangga, dan para pria (suami) menghasilkan ratarata 58%. (Berninghausen dan Kerstan 1992:103). Para peneliti mengadakan kalkulasi, kira-kira berapa prosentase para wanita di Gentuk yang akan mampu menghidupi keluarganya sendiri, andai kata suami tidak lagi menyerahkan penghasilannya. Menurut mereka, hal itu signifikan secara analitis dan praktis. Banyak sekali terjadi bahwa bila suami menceraikan isteri, yang terpaksa harus menghidupi anak-anak dan dirinya adalah isteri. Dengan menemukan angka ini, maka akan diketahui bagaimana posisi ekonomi dari wanita bila dibandingkan dengan suami mereka. Ternyata lebih dari sepertiga wanita di Gentuk, dengan perhitungan konsumsi beras untuk seorang dalam setahun 240 kg, dapat menghidupi sendiri keluarganya yang beranggotakan 5 orang. Jumlah pria (suami) yang mampu menghidupi sendiri keluarganya andai itu memang terjadi, sedikit lebih banyak, yaitu hampir 50%. Peranan wanita dalam menyediakan keperluan-keperluan dari keluarga ini adalah suatu fakta yang tidak dapat diingkari. Khusus untuk keluarga lapisan bawah, tidak ada yang menyangkal peranan wanita tersebut . Wanita juga memperoleh tugas untuk mengatur keuangan keluarga. Penghasilannya sendiri serta penghasilan dari para anggota keluarga lainnya tercakup dalam pengaturan wanita (istri). Namun, tidak terpikirkan oleh para wanita tersebut untuk menggunakan keuangan keluarga demi memuaskan kesenangannya sendiri. Norma bahwa seorang wanita mempunyai tugas untuk mengurus keluarga dan menyediakan keperluan-keperluan keluarga, begitu mengakar dalam diri mereka, sehingga mereka menganggap bahwa sudah semestinyalah mereka mengumpulkan harta untuk keperluan anak-anaknya. Karena itu, biaya-biaya untuk keperluan-keperluan keluarga akan diprioritaskan bila dihadapkan dengan kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri. Para pria diberikan kesempatan yang lebih banyak untuk menikmati kesenangan-kesenangan sendiri dan menghabiskan waktu untuk memuaskan keinginan-keinginannya sendiri dibandingkan dengan wanita. Karena itu, tidaklah mengherankan jika para pria atau suami menghabiskan lebih banyak uang untuk keperluan-keperluannya sendiri dibandingkan dengan isteri-isteri mereka. Banyak wanita yang dikaji di Gentuk mengeluh bahwa suami mereka menghamburkan harta keluarga untuk kesenangankesenangan pribadinya, padahal untuk menutupi kebutuhan paling dasar pun, penghasilan keluarga hampir tidak mencukupi. Para wanita 58 itu beranggapan bahwa hal itu merupakan ungkapan dari watak pria. Mereka tidak menyenanginya, tetapi menurut mereka watak itu tidak dapat diubah. Untuk membatasi kegemaran-kegemaran suami hingga ukuranukuran yang masih dapat diterima, mereka mengupayakan pola komunikasi yang diplomatis dengan suami, dan melakukan administrasi yang baik terhadap penghasilan keluarga. Demikianlah suatu contoh dari penelitian yang dilakukan dengan sengaja dan dirancang dengan keberpihakan pada wanita. Melalui penelitian dengan perspektif demikian, maka masalah-masalah wanita dapat terungkap dan akan dapat dipahami, sehingga kemudian dapat dicari upaya-upaya pemecahannya. Pengalaman-pengalaman wanita merupakan hal yang sangat penting. Pada penelitian berperspektif positivistik, pengalamanpengalaman semacam itu tidak dimunculkan sebagai topik yang wajar untuk diteliti. Akan terlihat bagaimana struktur masyarakat yang patriarkhis mendiskriminasi wanita, dan— melalui proses sosialisasi—para wanita menerima saja peran-peran yang sebenarnya diskriminatif tersebut. Pendekatan dengan perspektif feminis menempatkan manusia wanita sebagai pemeran keluarga, pemeran ekonomi yang penting, dan —bila sumbangannya dapat dimaksimalkan — akibat krisis dapat dipecahkan, mulai pada tingkat mikro untuk kemudian beranjak ke tingkat makro. Hak azasi wanita diperhatikan dan dihargai. Karena wanita menyangkut lebih dari 50 % jumlah rakyat Indonesia. Bila 50 % penduduk mengalami diskriminasi, tentu hal itu berdampak negatif bagi terwujudnya ketentraman dalam masyarakat. Ilmuwan yang berpihak pada manusia, yang tidak melepaskan tanggung jawab ilmiahnya— setelah mendeskripsikan hal-hal yang dikaji, menganalisis merumuskan kesimpulannya, serta terus turut memperjuang-kan agar terdapat upaya-upaya pemecahan masalah—akan besar sumbangsihnya dalam upaya pemecahan krisis ekonomi dan kondisi budaya bangsa. Penutup Krisis ekonomi yang dialami bangsa Indonesia telah secara nyata berdampak sangat buruk terhadap ekonomi rumah tangga, terutama ekonomi rumah tangga orang kecil. Dalam kenyataan, peranan ibu rumah tangga dalam kenyataan tidak terakomodasi dalam berbagai upaya pemecahan masalah. Krisis ekonomi itu pada dasarnya merupakan akibat dari salah urus di bidang ekonomi, korupsi pada berbagai tingkat birokrasi, kolusi dunia bisnis dengan birokrat yang sudah berlangsung lama. Kebijakan pembangunan yang top down memungkinkan hal-hal itu berlangsung subur. Kebijakan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan menyebabkan bahwa kepentingan rakyat menjadi terkesampingkan. 60 ANTROPOLOGI INDONESIA 60, 1999 Kepustakaan Berninghausen, J. dan B. Kerstan 1992 Forging New Paths: Feminist Social Methodology and Rural Women in Java. London and New Jersey: Zed Books Ltd. Gardiner, M.O. 1999 Women and Men at work in Indonesia. PT. Insan Hitawasana Sejahtera. Moore, H.L. 1988 Feminism and Anthropology. Minneapolis: The Univesity of Minnesota Press. Nielsen, J. Mc Carl (peny.) 1990 Feminist Research Methods: Exemplary Readings in the Social Sciences. Boulder, San Fransisco dan London: Westview Press. Sadli, S. dan S. Padmonodewo 1995 ‘Identitas Gender dan Peranan Gen der’, dalam T.O. Ihromi (peny.) Kajian Wanita dalam Pembangunan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal. 69-83. Sadli, S. dan M. Porter 1999 Metodologi Penelitian Berperspektif Perempuan dalam Riset Sosial. Jakarta, Program Studi Kajian Wanita UI. Sarantakos, S. 1992 Social Research. South Melbourne: Macmillan Education. Wilopo, S.A.dan S.M. Adioetomo 1999 The Impact of Crisis on Population and Reproductive Health in Indonesia. Jakarta: The State Ministry of Population in Collaboration with United Nations Population Fund. ANTROPOLOGI INDONESIA 60, 1999 60