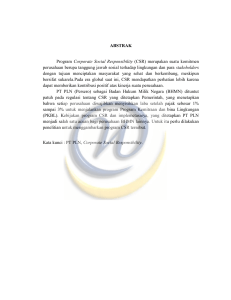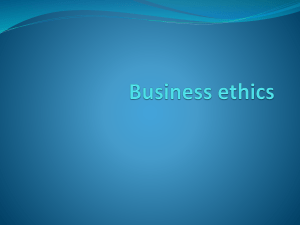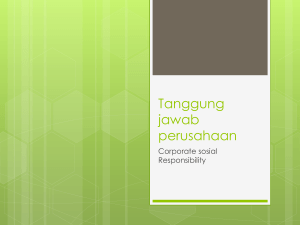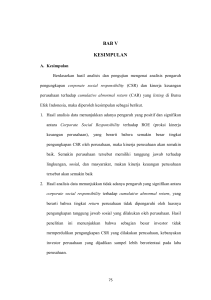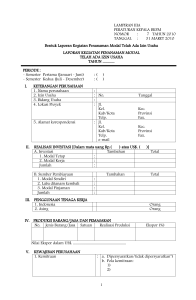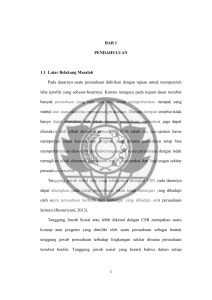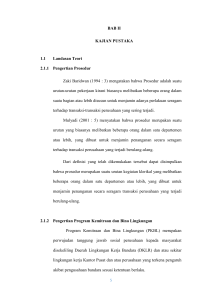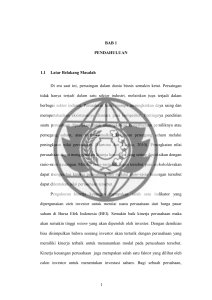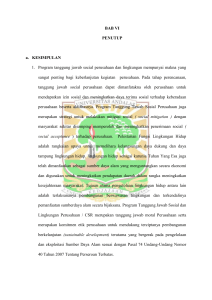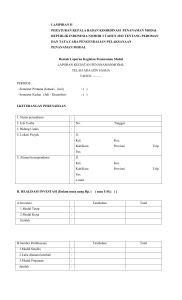2.1. Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR)
advertisement

39 BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) 2.1. Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai sebuah konsep yang populer, ternyata Corporate Social Responsibility belum memiliki pengertian yang benar-benar dapat dijadikan sebagi pedoman di dalam penerapannya atau dengan kata lain CSR belum memiliki definisi yang tunggal. Misalnya, World Business Council, sebuah lembaga internasional yang berdiri tahun 1995 dan beranggotakan lebih dari 120 perusahaan multinasional yang berasal dari 30 negara yang bergerak di bidang pembangunan berkelanjutan, memberikan definisi secara luas mengenai CSR. Dalam publikasinya yang berjudul “Making Good Business Sense” oleh Lord Holme dan Richard Watts, lembaga ini menjelaskan pengertian CSR sebagai berikut 40: “Corporate Social Responsibility is the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large”. Pengertian yang diberikan diatas, apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia secara bebas kurang lebih berarti: “komitmen dunia usaha untuk terus-menerus bertindak secara etis, beroperasi secara 40 Mallen Baker, 2004, Corporate Social Responsibility: What Does It mean?, News and Resources, www.mallenbaker.net, diakses tanggal 5 Agustus 2011. 40 legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan”. Lembaga lain, misalnya Bank Dunia memiliki pengertiannya sendiri mengenai Corporate Social Responsibility (CSR). Bank Dunia merumuskan Corporate Social Responsibility 41: “the commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development". Selanjutnya, Corporate didefinisikan oleh Uni Social Responsibility sebagaimana Eropa, lembaga perhimpunan negara-negara di benua Eropa, adalah: "CSR is a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basic". Apabila diterjemahkan secara bebas, CSR adalah suatu konsep dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan hidup dalam operasional usahanya dan dalam berinteraksi dengan para stakeholders yang didasari kesukarelaan. Masih berkaitan dengan pengertian CSR, menurut Yusuf Wibisono, CSR didefinisikan sebagai tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek 41 Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, 2008, Corporate Social responsibility: prinsip, Pengaturan dan Implementasi, Malang: In-Trans Publising, hlm. 29 41 ekonomi, sosial, dan lingkungan (triple bottom line) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. 42 Selain rumusan tersebut diatas, para ahli lain juga tidak ketinggalan memberikan definisi mengenai Corporate Social Responsibility, diantaranya penjelasan yang diberikan oleh, Michael Hopkins 43: “CSR is concerned with treating the stakeholders of the firm etchically or in a responsible manner. ‘Ethically or responsible’ means treating stakeholders in a manner deemed acceptable in civilized societies. Social includes economic responsibility, stakeholders exist both within a firm and outside. The natural environment is a stakeholder. The wider aim of social responsibility is to create higher standards of living, while preservinmg the profitability of the corporation, for people both within and outside the corporation”. Lebih jauh, menurut Soeharto Prawirokusumo, 44 tanggung jawab sosial adalah sebuah konsep yang luas yang berhubungan dengan kewajiban perusahaan atau organisasi dalam memaksimumkan impact positif terhadap masyarakatnya. Tanggung jawab sosial para pelaku usaha dalam suatu perusahaan terdiri atas empat dimensi tanggung jawab yaitu; ekonomi, hukum, etika dan philanthropies. Dari berbagai rumusan diatas, dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini belum ada kesamaan bahasa dalam merumuskan dan memaknai CSR sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Namun 42 Yusuf Wibisono, 2007, Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility, Jakarta: Fasco Publishing, hlm. 7. 43 Michel Hopkins, 2003, The Business Case For CSR: Where Are We?, International Journal for Business Performance Management, Vol. 5, No. 2, hlm. 125. 44 Soeharto Prawirokusumo, 2003, Perilaku Bisnis Modern – Tinjauan pada Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 22, No 4, hlm 83. 42 dari perbedaan pengertian yang disampaikan diatas dapat ditarik sebuah benang merah tentang elemen-elemen penting dari CSR, antara lain: (1) prilaku perusahaan atau masyarakat bisnis; (2) upaya mensinergiskan kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup; (3) membangun interaksi dengan stakeholder. Dalam penelitian ini lebih ditekankan pada penggunaan kerangka sustainable development theory dan triple bottom line theory yang mensyaratkan adanya keseimbangan dalam operasional perusahaan antara tujuan untuk mengakumulasi keuntungan dengan kebutuhan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan membangun interaksi harmonis dengan masyarakat. Akan tetapi yang sulit untuk dapat disepakati antara definisi satu dengan definisi yang lain adalah standar yang berkaitan dengan kekuatan pendorong CSR. Pengertian yang diberikan oleh Uni Europa misalnya, dengan tegas menyatakan bahwa CSR didasari oleh kesukarelaan. Sedangkan menggarisbawahi bahwa disisi CSR yang lain, merupakan Michael Hopkins tanggungjawab etis sehingga dapat diartikan sebagai sebuah kewajiban yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian apakah sebuah perusahaan bertindak etis atau tidak. Dalam konteks Indonesia, beragam pengertian tentang CSR dapat pula ditemukan dari beberapa ketentuan perturan perundangundangan yang ada. Jika dilakukan perbandingan antara UU 43 Penanaman Modal dengan UU Perseroan Terbatas, maka dapat dilihat perbedaan pengertian CSR sebagai berikut: 1. Penjelasan Pasal 15 huruf b Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 menegaskan tentang Penanaman Modal (UUPM) bahwa “tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat”. Jadi dapat disimpulkan bahwa, UU PM menekankan CSR sebagai upaya perusahaan untuk menciptakan harmonisasi dengan lingkungan di mana ia melakukan aktivitas usahanya. 2. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) menegaskan bahwa “tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”. Jadi, UU PT lebih menekankan CSR sebagai wujud komitmen perusahaan dalam mewujudkan konsep sustainable development. 44 Dari pengertian diatas, nampaknya tujuan dari CSR dalam UU PT jauh lebih luas karena meletakkan paradigma pembangunan berkelanjutan dan menjangkau pembangunan ekonomi nasional. Namun sayangnya bahasa yang digunakan oleh UU PM jauh lebih tegas yakni CSR dinilai sebagai ‘tanggung jawab yang melekat’ sedangkan dalam UU PT, CSR hanya dinilai sebatas ‘komitmen’ perusahaan. Selain itu, UU PT melihat bahwa CSR idealnya merupakan suatu ‘win-win solution’, dalam artian CSR tidak hanya menguntungkan perusahaan melainkan juga entitas lain di luar perusahaan seperti masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan tersebut berdiri. Karena keragaman pengertian tersebut, maka CSR seyogyanya tidak menyediakan didefinisikan framework yang secara sifatnya ketat melainkan fleksibel namun dengan tanpa merubah konsep awalnya sehingga dapat menyesuaikan diri dengan cepatnya laju perkembangan hukum bisnis. Terlepas dari keberagaman dan ketidakjelasan pengertian CSR, terdapat satu hal yang nampak jelas yakni CSR merupakan konsep yang mencoba mendorong kepedulian dan tanggung jawab dunia usaha terhadap lingkungan di sekitarnya. Kepedulian dan tanggung jawab ini pada tingkat yang paling minimal yakni tanggung jawab perusahaan terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan usahanya mulai dari dampak terhadap kesehatan, ekonomi, lingkungan, sampai sosial budaya dan hukum setempat. Sehingga 45 dalam mewujudkan tanggung jawab ini dalam bentuk praktek, perusahaan harus menggunakan strategi CSR yang tepat dalam melakukan intervensi terhadap dampak-dampak tersebut. 2.2. Sejarah dan Perkembangan Corporate Social Responsibility (CSR) Di awal kelahirannya konsep CSR ditentang oleh para penganut doktrin ekonomi klasik (kapitalis murni). Hal ini dikarenakan oleh pandangan dominan bahwa perusahaan tidak perlu melakukan tanggung jawab sosial karena pelayanan sosial merupakan tugas dari negara yang timbul dari pembayaran pajak sebagai kompensasi dari perusahaan kepada negara. Jadi fungsi perusahaan hanyalah bertugas untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa terbebani kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial. Pandangan ini juga dianut luas oleh Milton Friedman, bapak dari Neo-Liberalisme. Pada tahun 1962, Milton Friedman dalam bukunya yang berjudul: Capitalism and Freedom (Friedman 1992) dan salah satu tulisannya yang termuat dalam The New York Times Magazine (September 1970) 45 pada intinya berpendapat, bahwa satusatunya tujuan dari social responsibility perusahaan adalah memaksimalkan pendapatan dan kekayaan perusahaan bagi para pemegang 45 sahamnya. Berawal dari pendapat Friedman inilah Milton Friedman, 1970, The Social responsibility of Business is to Increase its Profits, The New York Times Magazine, http://www.colorado.edu/studentgroups/libertarians/issues/ friedman, diakses tanggal 5 Agustus 2011. hlm 1. 46 akhirnya banyak perusahaan yang bersikap anti sosial dan dalam banyak hal melakukan praktik yang eksploitatif terhadap pekerja dan lingkungan hidup dengan tujuan semata-mata untuk mengakumulasikan keuntungan. Dalam perkembangannya, banyak reaksi bermunculan dalam merespon praktek-praktek korporasi yang eksploitatf tersebut. Misalnya komunitas internasional mulai mendorong penghormatan dan pelindungan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) dalam operasi korporasi. Selain itu, sejak beberapa tahun terakhir ini organisasiorganisasi internasional ataupun di banyak negara juga memberikan perhatian pada tanggung jawab korporasi dan menerapkan Corporate Social Responsibility dengan tujuan sebagai kompetitif advantage (SHRM 2007). 46 Sebelumnya, pada dekade 1980 sampai 1990-an, wacana CSR terus mengalami perkembangan pesat. Salah satunya adalah pada Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (Earth Summit) di Rio pada 1992 yang menegaskan dan menyepakati bahwa terdapat kebutuhan untuk melakukan perubahan paradigma pembangunan dari pertumbuhan ekonomi (economic growth) menjadi pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Hal ini tidak hanya didorong untuk dilakukan oleh negara atau pemerintah tetapi juga menjadi pedoman bagi kalangan korporasi. Ada 5 hal penting yang disepakati terkait 46 Yusuf Wibisono, loc. cit. 47 dengan konsep keberlanjutan tersebut, yaitu: (1) ketersediaan dana, (2) misi lingkungan, (3) tanggung jawab sosial, (4) terimplementasi dalam kebijakan (masyarakat, korporat dan pemerintah), (5) mempunyai nilai keuntungan/manfaat. Terobosan besar dalam kontek CSR ini dilakukan oleh John Elkington melalui konsep "3P" (Profit, people, and planet). Konsep ini dituangkan dalam bukunya "Cannibals with Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business" yang dirilis pada tahun 1997 sebagaimana dikutip oleh Wayne Visser, et.al. 47 la berpendapat bahwa jika perusahaan ingin operasionalnya berlanjut (sustain), maka ia perlu memperhatikan 3P diatas. Jadi, perusahaan tersebut tidak bisa, cuma memburu profit semata, namun ia juga harus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat (people), dan ikut aktif dalam menjaga lingkungan hidup (planet). Selanjutnya, dalam pertemuan internasional Johannesburg pada tahun 2002 yang dihadiri para pemimpin dunia memunculkan konsep social responsibility. Konsep ini, melengkapi dua konsep yang ada sebelumnya yaitu economic growth dan environmental sustainability. Dalam perkembangannya, ketiga konsep ini menjadi dasar bagi perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya (Corporate Social Responsibility). Lebih lanjut, pada 7 Juli 2007 di Jenewa, Swiss, sebuah pertemuan bertema United Nations (UN) 47 Wayne Visser Et. al., 2010, The A-Z of Corporate Social Responsibility, UK: John Wiley & Sons Ltd, hlm. 406. 48 Global Compact dibuka Sekjen PBB bertujuan mendorong perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawab dan perilaku bisnis yang sehat yang dikenal dengan Corporate Social Responsibility. Di Indonesia, istilah CSR semakin populer digunakan sejak awal tahun 1990-an. Beberapa perusahaan sebenarnya telah melakukan CSA (Corporate Social Activity) atau “aktivitas sosial perusahaan”. Walaupun berbeda secara gramatikal, secara faktual aksinya mendekati konsep CSR yang merepresentasikan bentuk “peran serta” dan “kepedulian” perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan. Melalui konsep investasi sosial perusahaan “seat belt” 48, sejak tahun 2003 Departemen Sosial tercatat sebagai lembaga pemerintah yang aktif dalam mengembangkan konsep CSR dan melakukan advokasi kepada berbagai perusahaan nasional. 2.3. Perbandingan Konsep dan Perkembangan CSR Di tingkat internasional, terdapat banyak prinsip yang mendukung praktik CSR di banyak sektor bisnis. Kesadaran tentang pentingnya mengimplementasikan kecenderungan global seiring CSR dengan ini semakin juga menjadi meningkatnya kepedulian masyarakat global terhadap produk-produk yang ramah lingkungan dan diproduksi dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial dan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Gejala yang 48 Rosita Candra Kirana, 2009, Studi Perbandingan Pengaturan Tentang Corporate Social Responsibility di Beberapa Negara Dalam Upaya Perwujudan Prinsip Good Corporate Governance, Tesis Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 40. 49 biasa disebut dengan lahirnya kesadaran sebagai konsumen etis ini sudah banyak terjadi di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris ataupun Jerman. Menghadapi tren global dan masih marak terjadinya resistensi masyarakat sekitar perusahaan, maka sudah saatnya setiap perusahaan mempertimbangkan dengan serius pengaruh dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan dari setiap aktivitas bisnisnya. Selain itu, perusahaan juga diharapkan membuat laporan setiap tahunnya kepada stakeholder-nya. Laporan yang bersifat non financial ini akan dapat digunakan sebagai acuan perusahaan dalam melihat dimensi sosial, ekonomi dan lingkungannya. Dan sebaliknya, laporan tersebut juga dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam menilai perusahaan tersebut. Strategi melalui mekanisme pelaporan publik untuk mendorong tanggungjawab perusahaan telah banyak dilakukan di beberapa belahan dunia. Misalnya di Uni Eropa pada 13 Maret 2007, Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi berjudul “Corporate Social Responsibility: A New Partnership”. Resolusi ini mendesak Komisi Eropa untuk meningkatkan kewajiban yang terkait dengan persoalan akuntabilitas perusahaan seperti tugas direktur (directors’ duties), kewajiban langsung luar negeri (foreign direct liabilities) dan pelaporan kinerja sosial dan lingkungan perusahaan (environmental and social reporting). 50 Di Inggris, dikarenakan telah banyaknya aturan dan undangundang yang mengatur praktik bisnis di Inggris, maka regulasi khusus CSR sepertinya tidak diperlukan lagi. Sekedar diketahui, perusahaan di Inggris ini tidak lepas dari pengamatan publik (masyarakat dan negara) karena perusahaan diikat oleh kode etik usaha dan harus transparan dalam praktik bisnisnya. Terdapat mekanisme komplain yang bisa digunakan oleh publik untuk melakukan protes terbuka ke perusahaan yang dianggap merugikan masyarakat/ konsumen/buruh/lingkungan. Lebih jauh, tahun lalu pemerintah Inggris mensahkan Companies Act 2006 yang mewajibkan perusahaan yang sudah tercatat di bursa efek untuk melaporkan bukan saja kinerja perusahaan (kinerja ekonomi dan financial) melainkan kinerja sosial dan lingkungan hidup. Laporan ini harus terbuka untuk dapat diakses dan dilakukan penilaian oleh publik. Dengan demikian, perusahaan didesak agar semakin bertanggung jawab dalam operasi bisnisnya. Selain itu negara-negara seperti Australia, Kanada, Perancis, Jerman, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat telah mengadopsi code of conduct CSR yang meliputi aspek lingkungan hidup, hubungan industrial, gender, korupsi, dan hak asasi manusia (HAM). Berbasis pada aspek itu, mereka mengembangkan regulasi guna mengatur CSR. membuat laporan Australia, tahunan misalnya, CSR dan mewajibkan mengatur perusahaan standardisasi 51 lingkungan hidup, hubungan industrial, dan HAM. Sementara itu, Kanada mengatur CSR dalam aspek kesehatan, hubungan industrial, proteksi lingkungan, dan penyelesaian masalah sosial. Jadi, penerapan CSR di beberapa negara dapat dijadikan referensi dalam mendorong penerapan CSR di Indonesia. Oleh karena itu penting sekiranya melihat secara lebih jauh konsep CSR dalam konteks nasional di beberapa kawasan yang secara ekonomi dan budaya korporasinya telah cukup maju sembari dibandingkan dengan kondisi di Indonesia sendiri. 2.3.1. CSR di Eropa Menurut European Commission (Komisi Eropa), CSR adalah konsep dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan atas dasar sukarela. Di Eropa, perusahaan menjalankan CSR memiliki tujuan dan strategi yang selaras dengan tujuan strategis untuk Eropa 2010 yang didefinisikan pada KTT Lisbon 49: “to turn Europe into the most competitive and dynamic knowledge based economy in the world by 2010”. Terlepas dari adanya berbagai praktik CSR baik dalam sektor bisnis dan negara, sebenarnya pendekatan terhadap konsep CSR secara formal di Eropa sendiri belumlah ditetapkan. 49 www.csreurope.org., di akses tanggal 10 Agustus 2011. 52 Namun, sebuah Roadmap Eropa untuk bisnis 2010 telah diluncurkan pada 2005 sebagai sebuah inisiatif yang dipimpin oleh sebuah lembaga bernama CSR Europe bersama perusahaanperusahaan yang menjadi National Partner Organisations-nya di seluruh negara-negara Eropa. Kegiatan yang didorong dalam Roadmap tersebut diharapkan dapat berkontribusi terhadap Strategi Lisbon dalam mendorong hal sebagai berikut 50: • Sebuah visi yang jelas untuk kontribusi Eropa menuju usaha yang berkelanjutan dan kompetitif di Eropa. • Komitmen untuk Enterprise Eropa yang berkelanjutan dan kompetitif • Daya tarik bisnis untuk Uni Eropa, pemerintah dan pemangku dengan kepentingan bisnis dalam dilibatkan bersama-sama pencapaian pembangunan berkelanjutan di Eropa. Para stakeholder yang secara eksplisit disebutkan adalah karyawan dan perwakilan mereka, organisasi konsumen dan organisasi non pemerintah, investor, akademisi, dekan dan guru. Berkaitan dengan penerapan CSR di Eropa, tentu saja memiliki karakteristik tersendiri dari tempat yang lain. Adapun 50 Ibid. 53 karakteristik dari bentuk Corporate Social Responsibility di Eropa adalah sebagai berikut 51: a. Bisnis yang memiliki kepemimpinan yang kuat dan keterlibatannya dalam CSR. Setelah meluncurkan Roadmap Eropa tentang CSR, kegiatan bisnis mulai menunjukkan antusiasme yang besar untuk berpartisipasi dalam Aliansi Eropa mengenai CSR, yang dilakukan pada Maret 2006. Aliansi ini adalah sebuah jaringan yang bersifat terbuka bagi perusahaan-perusahaan Eropa, yang diluncurkan oleh Komisi Eropa pada tahun 2006 dalam rangka untuk mempromosikan dan mendorong CSR lebih jauh. Aliansi ini pula merupakan payung politik untuk inisiatif CSR oleh perusahaan besar, perusahaan kecil dan menengah, serta para pemangku kepentingan. b. Keanekaragaman istilah dan bentuk CSR di negaranegara Eropa yang secara tematik bergantung pada situasi politik dan ekonominya. Elemen-elemen kunci yang menentukan keragaman pendekatan-pendekatan dalam penerapan CSR, yakni: 51 ibid 54 • Faktor-faktor kontekstual seperti sosial politik, demografi, kelembagaan dan perkembangan teknologi; • Strategi dalam melakukan intervensi CSR yang diadopsi oleh kalangan bisnis, termasuk di dalamnya pertimbangan yang berkaitan dengan efisiensi reputasi, kepercayaan dan operasional; • Dinamika stakeholder yang menjadi dasar bagi kalangan bisnis untuk melakukan intervensi termasuk di dalamnya tekanan eksternal stakeholder seperti investor dan LSM. c. Komisi Eropa dan pemerintah nasional dari negaranegara anggota Uni Eropa memainkan peranan yang berbeda dan saling melengkapi dalam mempromosikan CSR. Pada tahun 2001, Komisi Eropa mengeluarkan kebijakan mengenai Green Paper untuk mulai pembahasan terkait konsep CSR dan bagaimana mempromosikannya. Saat ini, justru perusahaan memegang peranan utama dalam mendorong lembaga CSR Europe untuk berada di garis depan penerapan 55 CSR secara global dan pengaturan agenda bisnis yang bertanggung jawab dan kompetitif di Eropa. Khusus pengaturan CSR di Eropa, dapat dilihat dari pengaturannya oleh salah satu negara anggota Uni Eropa, misalnya Inggris. Inggris memiliki the 2003 Corporate Responsibility Bill yang merupakan respon atas kegagalan penerapan White Paper on Modernising Company Law yang mengatur tentang transparansi atau akuntabilitas perusahaan kepada stakeholder. Pasal Bill tersebut 2 dari Corporate Responsibilty mengatur tentang penerapan ekstrateritorial CSR di semua bidang, kewajiban perusahaan untuk stakeholder, dan melakukan konsultasi membebankan dengan kewajiban bagi perusahaan untuk menyiapkan dan mempublikasikan laporan perusahaan. Pasal 7 dan 8 menekankan pada kewajiban direksi terhadap sosial dan lingkungan. Pasal 6 membebankan perusahaan merger, induk tanggung terhadap pembagian, akuisisi anak dan jawab kepada perusahaannya, restrukturisasi lainnya yang menyebabkan kerugian bagi seseorang atau lingkungan hidup di wilayah Inggris. 56 Hal yang sama juga dilakukan oleh legislasi Inggris Raya dalam hal investasi dana pensiun. Dipersyaratkan bahwa setiap investasi dana pensiun harus memasukkan sosial, lingkungan, penyimpanan dan pertimbangan-pertimbangan atau etis penerapan dalam investasi pemilihan, tersebut. 52 Selain itu, keterlibatan pemangku kepentingan yang merupakan ciri penting dari CSR Eropa juga menjadi proses prosedural yang harus diikuti dalam praktek investasi. 2.3.2. CSR di Amerika Di Amerika konsep Corporate Social Responsibility lebih dikenal dengan Corporate Citizenship. 53 Corporate Citizenship sendiri dapat didefinisikan sebagai usaha untuk memperluas memasukkan lingkungan hubungan antara pemahaman dan politik. bisnis tentang Konsep dan masyarakat tanggung ini juga guna jawab sosial, melihat bahwa perusahaan memiliki tugas, hak dan tanggung jawab karena perusahaan diperlakukan sebagai anggota masyarakat biasa 52 Illias Bantekas, 2004, Corporate Social Responsibility in International Law, 22 Boston University International Law Review, hlm 326. 53 Rosita, 2010, Corporate Social Responsibility, Blog Archive, www.rosita.staff.uns.ac.id. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2010. 57 seperti halnya warga negara pada umumnya yang terlibat dan berpartisipasi dalam berbagai bentuk pemerintahan masyarakat. Dalam pandangan teori korporasi klasik di Amerika Serikat, CSR dimaknai sebagai tanggung jawab para manajer dan direksi kepada pemegang saham. Pandangan tradisional ini tidak mencakup kewajiban manajemen untuk memperhatikan kepentingan konstituen perusahaan yang berada diluar manajemen dan pemegang saham. Hal ini membatasi penerapan CSR menjadi praktek yang terjadi secara internal atau dalam perusahaan semata sehingga memunculkan anggapan bahwa perusahaan sebagai entitas yang egostik karena seolah-olah hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri. 54 Istilah Corporate Citizenship sendiri telah digunakan Amerika Serikat sebagai referensi untuk filantropi perusahaan. Namun istilah tersebut baru memperoleh pengakuan dan pengertiannya berubah secara radikal sebagai tanggung jawab perusahaan pada 1990-an. Hal ini terjadi ketika di Eropa Perusahaan Corporate Citizenship dibentuk pada tahun 1997 dan, berbagai dunia akademik di Inggris, Jerman, AS dan Australia membentuk pusat-pusat kajian Corporate Citizenship dan pada 2001 menerbitkan Journal of Corporate Citizenship. 55 54 Gary von Stange, 1994, Corporate Social Responsibility through Constituency Statutes: Legend or Lie ?, 11 Hofstra Labour Law Journal, hlm 465. 55 Malcolm McIntosh dalam Wayne Visser Et. al. 2010, loc. cit, h. 88. 58 Selain itu pula, pada 2001 inisiatif seperti UN Global Compact menyebutkan tentang Corporate Citizenship. Istilah ini dimaksudkan sebagai model bisnis yang memasukkan keprihatinan terhadap hak asasi manusia, standar tenaga kerja dan perlindungan lingkungan sebagai nilai-nilai dasar dari pengoperasian strategi bisnis. Sehingga corporate citizenship dapat digambarkan sebagai sebuah metafora aspiratif bagi perusahaan untuk terlibat dalam pengembangan dunia yang lebih baik, yaitu sebagai upaya perusahaan untuk meningkatkan kepedulian terhadap masalah sosial dan lingkungan dalam kegiatan usahanya dan juga pada cara perusahaan berinteraksi dengan stakeholder yang dilakukan secara sukarela. 2.3.3. CSR di Indonesia Perusahaan-perusahaan di Indonesia lebih sering menerapkan bentuk community development sebagai salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan yang mengedepankan konsep ini akan lebih menekankan pada pembangunan sosial dan pembangunan kapasitas masyarakat sehingga akan menggali potensi masyarakat lokal yang menjadi modal sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Dewasa ini dengan adanya kemajuan informasi dan teknologi serta desakan globalisasi, tuntutan perusahaan untuk 59 menjalankan CSR semakin besar. Karena setidaknya ada tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha mesti merespon dan mengembangkan isu tanggung jawab soaial sejalan dengan operasi usahanya, yaitu: a. Perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat; b. Kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme; c. Kegiatan tanggung jawab sosial merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindari konflik sosial. Sifat CSR yang sukarela, absennya produk hukum yang dapat memberikan kejelasan kriteria dalam penerapan CSR ditambah dengan lemahnya penegakan hukum telah menjadikan Indonesia sebagai negara ideal bagi korporasi yang memang memperlakukan CSR sebagai ‘kosmetik’. 56 Dengan demikian, demi keberhasilan dalam melakukan program CSR sebenarnya, diperlukan komitmen yang kuat, partisipasi aktif semua pihak yang peduli terhadap program CSR karena program ini begitu penting sebagai bentuk kewajiban perusahaan untuk bertanggung 56 Mas Achmad Daniri, 2005, Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapnnya Dalam Konteks Indonesia, Jakarta: PT. Ray Indonesia, hlm. 14. 60 jawab atas keutuhan kondisi-kondisi masyarakat dan lingkungan sekitar. 2.4. Dunia Usaha, Etika Bisnis dan Masyarakat 2.4.1. CSR dan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam perusahaan telah menjadi Perserikatan suatu Bangsa mengakomodasi pembangunan isu yang Bangsa berbagai berkelanjutan, kontroversial (PBB). pendapat serta Sebagai dalam forum upaya untuk mengenai untuk konsep memperkuat implementasi kebijakan, Sekretaris Jenderal PBB pada saat itu yaitu Kofi Annan, 57 meluncurkan “The Global Compact” pada bulan Juni 1999. Melalui Global Compact tersebut, Annan menantang kalangan bisnis secara langsung untuk berkontribusi pada “keberlanjutan” dan “globalisasi”. Pembangunan berkelanjutan dianggap sebagai paradigma pembangunan yang sangat ambisius karena mencakup semua hal yang secara inheren menyiratkan konflik kepentingan dalam masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Gjolberg, “achieving sustainable development presupposes – given the 57 Maria Gjolberg and Audun Ruud, 2005, Working Paper: The UN Global Compact- A Contribution to Sustainable Development?, Centre for Development and the Environment University of Oslo, hlm. 7 61 existence of situations of irreconcilable conflicts of interest – the use of binding, and not only voluntary measures”. 58 Dengan pembangunan demikian jelas berkelanjutan bahwa dalam dibutuhkan mencapai kewajiban yang mengikat karena pelaksanaan sukarela dipercaya tidak akan mampu mendamaikan lingkungan yang kepentingan sering kali ekonomi, berkonflik satu sosial dan sama lain sebagaimana diungkap oleh Gjolberg diatas. Selain itu, untuk mewujudkan suatu pembangunan berkelanjutan, pasti akan menimbulkan suatu keadaan atau situasi kalah atau menang. Dalam konteks perusahaan, pembangunan berkelanjutan menekankan pada perubahan bottom line ekonomi yang selama ini menjadi dasar yang dominan dalam operasional mereka. Dalam situasi ini, setidaknya dalam jangka waktu yang pendek akan terdapat kerugian ekonomi dari perusahaan akibat dari penerapan perubahan yang dimaksud untuk mengakomodir bottom line sosial dan lingkungan hidup sukarela. Definisi pembangunan berkelanjutan sendiri diberikan oleh WCED (World Commission on Environment and Development) tahun 1987 dalam laporannya berjudul “Our Common Future”. Komisi ini berusaha untuk mengatasi konflik 58 Ibid. 62 antara kepentingan untuk melakukan pelestarian lingkungan dan tujuan pembangunan dengan merumuskan definisi pembangunan berkelanjutan sebagai berikut 59 : “Sustainable development is development which meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”. (pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengkompromikan kemampuan dari generasi berikutnya dalam memenuhi kebutuhan mereka) Setelah melalui diskusi yang panjang, akhirnya disepakati adanya 3 aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan, yakni: • Aspek Ekonomi: dimana suatu sistem ekonomi berkelanjutan harus mampu menghasilkan barang dan jasa secara berkesinambungan dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan sistem sektoral yang mengakibatkan rusaknya sistem pertanian dan industri. • Aspek Lingkungan: suatu sistem keberlanjutan lingkungan harus mampu mempertahankan sumber daya alam secara stabil, menghindari over eksploitasi sumber daya alam termasuk didalamnya pemeliharaan keanekaragaman 59 Ibid. hayati, stabilitas atmosfer, dan 63 pelestarian fungsi ekosistem lainnya yang tidak bisa digolongkan sebagai sumber daya ekonomi. Aspek Sosial: sebuah sistem sosial yang berkelanjutan • harus mampu memadai, mencapai penyediaan ekuitas distribusi pelayanan sosial secara termasuk kesehatan dan pendidikan, kesetaraan gender, dan akuntabilitas partisipasi dalam politik. Dalam konteks perusahaan, sustainability merupakan salah satu tujuan utama dari semua perusahaan. Dalam mencapai tujuan ini perusahaan juga harus berupaya keras untuk menyeimbangkan antara kinerja ekonomi, kesejahteraan sosial (well-being), dan peremajaan serta pelestarian lingkungan hidup yang terkait dalam proses produksinya. Salah satu upaya untuk mencapai keseimbangan ini yakni dengan jalan menerapkan program-program CSR. Jadi dapat disimpulkan bahwa CSR berkaitan erat dengan upaya dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Dengan kata lain, CSR dapat dianggap sebagai “vehicle” (kendaraan) guna mengintegrasikan kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan yang selama ini dianggap berbenturan satu dengan yang lain. Pemilihan bentuk misalnya melalui pelaksanaan program dari CSR penanaman oleh perusahaan pohon mempunyai 64 dampak langsung terhadap usaha pelestarian lingkungan yang menjadi salah satu pilar dalam pembangunan berkelanjutan. 2.4.2. Peran CSR dalam Mencapai MDGs (Millenium Development Goals) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2000 telah mencanangkan delapan tujuan yang hendak dicapai negaranegara di dunia untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran global. Impian itu dikenal dengan nama tujuan pembangunan milenium atau Millenium Development Goals (MDGs) dengan target pencapaian pada 2015. Adapun delapan sasaran MDGs tersebut adalah: (1) menghapus kemiskinan dan kelaparan, (2) pendidikan untuk semua orang, (3) promosi kesetaraan gender, (4) penurunan kematian anak, (5) meningkatkan kesehatan ibu, (6) memerangi HIV/AIDS, (7) menjamin keberlanjutan lingkungan, dan (8) kemitraan global dalam pembangunan. Sejatinya, CSR dapat berkontribusi dalam pencapaian kedelapan terget MDGs diatas. Misalnya, melalui pelaksanaan CSR dalam bentuk program pembuatan pendidikan di daerah terpencil yang pembangunan saat dari ini sulit pemerintah, dijangkau berarti oleh program perusahaan yang melaksanakan CSR ini telah membantu pemerintah dalam 65 mencapai target nomor 2 yakni pelayanan pendidikan secara universal. Begitu juga dengan program CSR dalam penyediaan obat Anti-Retroviral sebegaimana banyak (ARV) bagi dilakukan oleh penyandang HIV/AIDS organisasi filantropis seperti Bill and Melinda Gates Foundation yang merupakan program CSR dari perusahaan raksasa Microsoft mempunyai dampak langsung terhadap pencapain target pembangunan global khususnya dalam upaya memerangi HIV/AIDS. Berdasarkan alasan tersebut, maka semakin menguatkan bahwa CSR merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan dalam upaya mencapai target pembangunan millenium (MDGs). Namun permasalahannya disini adalah berapa banyak perusahaan yang mampu melaksanakan program CSR secara sukarela dan berdampak signifikan sebagaimana yang dilakukan oleh Microsoft. Hal ini akan berkaitan erat dengan pertanyaan apakah CSR merupakan kegiatan sukarela (voluntary) atau kegiatan yang wajib (mandatory) dilakukan oleh sebuah perusahaan. Jika CSR merupakan kegiatan sukarela, maka sebuah perusahaan mempunyai kebebasan dalam menentukan sikapnya apakah ia akan berkontribusi dalam membantu pencapain MDGs atau tidak dan tidak ada entitas luar yang bisa memaksa perusahaan tersebut untuk melakukannya. Oleh karena itu, 66 paradigma CSR haruslah dipertegas namun bukan dengan memisahkan antara aspek voluntary atau mandatory dari CSR. Melainkan kedua hal tersebut dijalankan lewat suatu formulasi yang saling melengkapi sebagai wujud tanggung jawab perusahaan atas segala dampak pembangunan yang didasarkan atas ‘mental frontier’ 60 yang mereka lakukan selama ini. 2.4.3. CSR Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Indonesia kekeluargaan menganut dan sistem berdasarkan perekonomian demokrasi berasaskan ekonomi dimana Pancasila menjadi landasan filosofisnya. Dalam konteks CSR sebagai bentuk kegiatan ekonomi dan bisnis, maka pelaksanaan dan pengaturan CSR sebenarnya tidak terlepas dari prinsip dan landasan filosofis sistem perekonomian nasional tersebut. Secara hirarki peraturan perundangan di Indonesia, prinsip CSR ini sesuai dengan maksud dan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana yang termaktub dalam preambul UUD 1945 yang menegaskan bahwa: ”...........Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial......” 60 Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, 2008, op. cit, h. 121. 67 Selain dalam pembukaan diatas, batang tubuh UUD 1945 juga memiliki relevansi dalam memberikan landasan hukum bagi CSR khususnya Pasal 33 ayat (1) dan (4) yang berbunyi: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi efisiensi ekonomi dengan berkeadilan, lingkungan, keseimbangan berkelanjutan, kemandirian, kemajuan prinsip serta dan kebersamaan, berwawasan dengan menjaga kesatuan ekonomi nasional. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa terjadi pergeseran penafsiran terhadap karakteristik CSR di Indonesia. CSR yang pada awalnya merupakan program pelayanan sosial perusahaan yang bersifat sukarela dapat ditafsirkan menjadi program yang wajib dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Jadi, tidak ada alasan bagi perusahaan untuk tidak melaksanakan prinsip CSR dalam aktivitas usahanya karena setiap aktivitas usaha harus memiliki prinsip sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 33 ayat (4) diatas. Namun terdapat kebutuhan untuk menterjemahkan landasan hukum diatas menjadi peraturan perundangan yang lebih operasional untuk membuat kewajiban tersebut menjadi bersifat imperatif. Pada titik inilah UU No. 40 tahun 2007 68 tentang Perseroan Terbatas dilahirkan dengan memasukkan klausul CSR pada Pasal 74. Pada prakteknya, pelaksanaan aturan terkait CSR di Indonesia dilengkapi pula oleh peraturan perundang-undangan yang lain. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan dapat berjalan selaras dalam mendukung dan memberikan efek yang positif terhadap pelaksanaan CSR di Indonesia. Beberapa undang-undang yang dimaksud adalah UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta peraturan-peraturan pemerintah tentang BUMN dan yang terkait lainnya. Keterkaitan antara aturan tentang CSR dengan UU tersebut diatas merupakan hal yang vital dalam mencapai tujuan CSR yang lingkungan diharapkan. Misalnya hidup, PPLH UU di bidang penyelamatan memperkenalkan instrumen ekonomi lingkungan hidup menjadi salah satu strategi untuk mendorong pemerintah, perusahaan dan masyarakat menlakukan pelestarian lingkungan. Pada Pasal 42 UU PPLH diatur beberapa bentuk instrumen ekonomi lingkungan hidup ini termasuk di dalamnya ayat (2) huruf (c) insentif dan/atau disinsentif. Selanjutnya pendekatan insentif/disinsentif ini dijabarkan oleh 69 Pasal 43 ayat (3) salah satunya melalui sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi dapat ditafsirkan disini bahwa CSR menjadi alat ukur untuk menilai layak atau tidaknya sebuah perusahaan mendapatkan penghargaan kinerja dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga dari penilaian berdasarkan kegiatan CSR perusahaan tersebut, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan insentif/disinsentif terhadap perusahaan yang dimaksud misalnya melalui pengurangan pajak atau sebaliknya memberikan peringatan. Selajutnya, pengaturan CSR yang ada di Indonesia masih bersifat sempit. Hal ini dapat dilihat dari cakupan CSR yang hanya mewajibkan perusahaan yang bergerak dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam saja untuk menyelenggarakan CSR. Sehingga perusahaan-perusahaan yang tidak memanfaatkan sumber daya alam secara langsung ditafsirkan tidak wajib melakukan CSR. Hal ini pada gilirannya akan berkaitan dengan mekanisme pelaporan tahunan perusahaan karena perusahaan yang dimaksud dalam Pasal 74 UUPT akan memiliki kewajiban untuk melaporkan kegiatan tahunan CSR-nya kepada Badan Pasar Modal. Akan tetapi belum ada ketegasan dari pemerintah sendiri mengenai seberapa penting laporan tahunan perusahaan 70 tersebut mengingat hingga saat belum ada cukup kesadaran bagi perusahaan untuk melaporkan kegiatan CSR mereka. Pengungkapan CSR yang telah dilakukan perusahaan memang sudah diatur dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) c. Pengungkapan tersebut dengan jalan pencantuman kegiatan CSR dalam laporan tahunan perusahaan. Adapun Pasal 66 tersebut berbunyi sebagai berikut: (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang kurangnya: (c). laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Aturan tentang laporan tahunan dalam UU Perseroan Terbatas memang belum tegas untuk menekan perusahaan dalam melaksanakan CSR. Bahkan tidak terdapat kejelasan terkait sanksi atau peringatan yang dapat diberikan kepada perusahaan yang tidak mencantumkan CSR dalam laporan tahunannya. Terlebih lagi ternyata laporan tahunan dengan mencantumkan CSR dianggap bukan merupakan hal yang prioritas bagi kepentingan perusahaan. Hal tersebut harus menjadi bahan 71 koreksi bahwa pentingnya pencantuman CSR dalam laporan tahunan untuk diatur lebih tegas lagi ke depan dan juga dibutuhkan kontrol dari pemerintah serta masyarakat akan kinerja CSR perusahaan di Indonesia. Karena secara tidak langsung laporan tahunan dapat menjadi bukti pemberian legitimasi dari masyarakat penerima manfaat CSR terhadap eksistensi dan kinerja suatu perusahaan. 2.4.4. Motivasi dan Prinsip Pelaksanaan CSR Setidaknya ada tiga alasan mengapa kalangan dunia usaha melaksanakan CSR sejalan dengan operasi perusahaannya. Ketiga alasan itu dapat digolongkan sebagai berikut: a. Pulic Relations Usaha untuk komunitas menanamkan terhadap persepsi kegiatan yang positif kepada dilakukan oleh perusahaan. b. Strategi Defensif Usaha yang dilakukan perusahaan guna menangkis anggapan negatif komunitas yang sudah tertanam dalam kegiatan perusahaan, dan biasanya untuk melawan ‘serangan’ negatif dari anggapan komunitas. Usaha CSR 72 yang dilakukan adalah untuk merubah anggapan yang berkembang sebelumnya dengan menggantinya dengan anggapan baru yang sifatnya positif. c. Kegiatan yang berasal dari visi perusahaan Melakukan program untuk kebutuhan komunitas sekitar perusahaan atau kegiatan perusahaan yang berbeda dari hasil perusahaan itu sendiri. Carroll 61 menggambarkan CSR dalam sebuah piramid yang terdiri dari empat struktur tanggung jawab; ekonomi, hukum, etika, dan filantrofi. Keempatnya merupakan kesatuan utuh CSR dan idealnya dijalankan dari yang paling dasar. Dua struktur di bawah harus dijalankan terlebih dahulu, sebelum memenuhi dua struktur berikutnya. Perkembangan CSR juga tidak bisa lepas dari konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development), definisi pembangunan berkelanjutan menurut The Brundtland Comission, adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka. The Brundtland Comission merupakan komisi yang dibentuk untuk menanggapi meningkatnya 61 keprihatinan dari para pemimpin dunia Archie B. Caroll, 1999, Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct, Business and Society, http://bas.sagepub.com/, diakses pada tanggal 30 Agustus 2011, hlm. 289. 73 menyangkut peningkatan kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang semakin cepat. Selain itu komisi ini mencermati dampak kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam terhadap ekonomi dan pembangunan sosial. Pengenalan konsep Sustainable Development memberikan dampak kepada perkembangan definisi dan konsep CSR. The Organization (OECD) for Economic merumuskan CSR Cooperation sebagai and kontribusi Development bisnis bagi pembangunan berkelanjutan serta adanya perilaku korporasi yang tidak semata-mata menjamin adanya pengembalian investasi dan keuntungan bagi pemegang saham, upah bagi para karyawan, dan pembuatan produk serta jasa bagi para pelanggan, melainkan perusahaan bisnis juga harus memberi perhatian terhadap berbagai hal yang dianggap penting serta nilai-nilai yang ada di masyarakat. Setidaknya terdapat tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha harus merespon CSR agar sejalan dengan jaminan keberlanjutan operasional perusahaan. Alasan tersebut adalah: Pertama, perusahaan adalah bagian dari masyarakat, oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. beroperasi Perusahaan dalam harus tatanan menyadari lingkungan bahwa sosial mereka masyarakat. Kegiatan sosial oleh perusahaan disini dapat berfungsi sebagai 74 kompensasi atau upaya timbal balik atas pemanfaatan sumber daya alam atau sumber daya ekonomi oleh perusahaan yang sering kali bersifat ekspansif dan eksploitatif. Kedua, kalangan bisnis dan masyarakat semestinya memiliki hubungan yang bersifat saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, wajar bila perusahaan dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sehingga bisa tercipta harmonisasi hubungan bahkan pengangkat citra dan performa perusahaan. Ketiga, kegiatan CSR merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindarkan perusahaan dari konflik sosial. Potensi konflik itu bisa berasal dari dampak operasional perusahaan atau akibat kesenjangan struktural dan ekonomis yang timbul antara masyarakat dengan komponen perusahaan. Pada hakikatnya CSR adalah nilai yang melandasi aktivitas perusahaan. Hal ini dikarenakan CSR menjadi pijakan komprehensif ekonomi, perusahaan sosial, dalam kesejahteraan mempertimbangkan dan lingkungan aspek hidup. Perusahaan semestinya tidak mengimplementasikan CSR secara parsial, misalnya berupaya memberdayakan masyarakat lokal, sedangkan di sisi yang lain, secara internal kesejahteraan karyawannya sendiri tidak terjamin, perusahaan tersebut tidak 75 disiplin dalam membayar pajak, menumbuh-suburkan praktik korupsi dan kolusi, atau mempekerjakan anak di bawah umur. Oleh karena itu, CSR di dalamnya mencakup empat landasan pokok yang satu dengan lainnya saling berkaitan, yakni: a. Landasan pokok CSR dalam aktivitas ekonomi, meliputi: kinerja keuangan berjalan baik, investasi modal berjalan sehat, kepatuhan dalam pembayaran pajak, tidak terdapat praktik suap/korupsi, tidak ada konflik kepentingan, tidak dalam keadaan mendukung rezim yang korup, menghargai hak atas kemampuan intelektual/paten, dan tidak melakukan sumbangan politis/lobi untuk memuluskan usahanya, b. Landasan pokok CSR dalam isu lingkungan hidup, meliputi: tidak berkontribusi melakukan dalam pencemaran, perubahan iklim, tidak tidak berkontribusi atas limbah diatas ambang batas, tidak melakukan pemborosan air, tidak melakukan praktik pemborosan energi, tidak melakukan penyerobotan lahan, tidak berkontribusi dalam kebisingan, dan menjaga keanekaragaman hayati 76 c. Landasan pokok CSR dalam isu sosial, meliputi: menjamin kesehatan karyawan atau masyarakat yang terkena dampak, tidak mempekerjakan anak, memberikan dampak positif terhadap masyarakat, melakukan proteksi konsumen, menjunjung keberanekaragaman, menghormati hak asasi manusia, menjaga privasi, melakukan praktik derma sesuai dengan kebutuhan, bertanggung jawab dalam proses outsourcing dan off-shoring, dan akses untuk memperoleh barang-barang tertentu dengan harga wajar d. Landasan pokok CSR dalam isu kesejahteraan, meliputi: memberikan kompensasi terhadap karyawan, memanfaatkan subsidi dan kemudahan yang diberikan pemerintah, menjaga kesehatan karyawan, menjaga keamanan kondisi tempat kerja, menjaga keselamatan dan kesehatan kerja, dan menjaga keseimbangan kerja/hidup Selain itu perusahaan bukanlah sebuah entitas tunggal, melainkan ia menjadi bagian dari pemangku kepentingan (stakeholder). Secara sederhana definisi stakeholder adalah kelompok-kelompok yang mempengaruhi dan/atau dipengaruhi 77 oleh organisasi tersebut sebagai dampak dari aktifitas- aktifitasnya. Stakeholder terdiri dari: a. Pelanggan: berhak mendapatkan produk/pelayanan berkualitas, dan layak. b. Masyarakat: berhak mendapatkan perlindungan dari kejahatan bisnis, dan mendapatkan hubungan yang baik dari keberadaan perusahaan c. Pekerja: berhak mendapatkan jaminan keamanan dalam bekerja, mendapatkan mendapatkan jaminan perlakukan keselamatan, yang adil dan dan non diskriminasi d. Pemegang Saham: berhak mendapatkan harga saham yang layak dan keuntungan saham. e. Lingkungan: berhak mendapatkan jaminan terhadap perlindungan alam, dan mendapatkan rehabilitasi f. Pemerintah: berhak mendapatkan laporan atas pemenuhan persyaratan hukum g. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): berhak menjalankan fungsi kontrol baik terhadap regulasi maupun komitmen perusahaan. Dalam dirangkul dan konteks penerapan dilibatkan baik CSR, dalam stakeholder tahap wajib perencanaan, implemantasi dan evaluasi. Jikapun stakeholder tidak dilibatkan 78 dalam proses perencanaan, setidaknya mendapatkan kontribusi berupa dampak positif dari program yang dilaksanakan. Andai terdapat satu stakeholder yang tidak mendapatkan manfaat atau kepuasan dari perusahaan, maka akan berpotensi masalah bagi keberlanjutan perusahaan dikemudian hari. menjadi