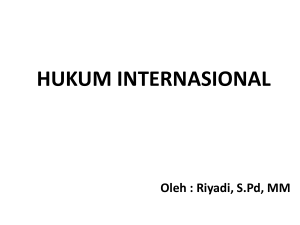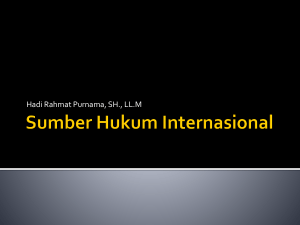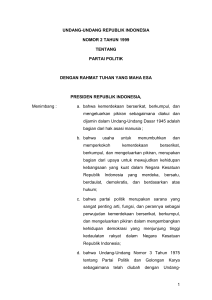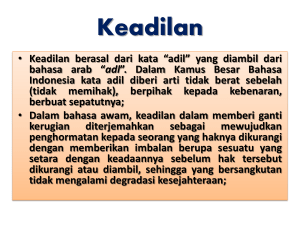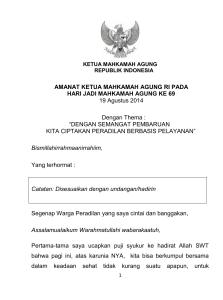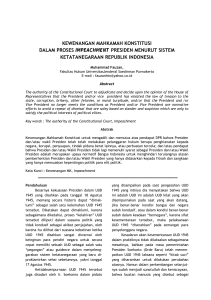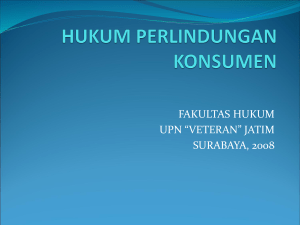Dilematika Putusan Mahkamah Konstitusi vs Kekuatan Politik dalam
advertisement

Dilematika Putusan Mahkamah Konstitusi vs Kekuatan Politik dalam Impeachment Presiden Nadir Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan Jl. Raya Panglegur km. 3,5 Pamekasan Madura Jatim Email: [email protected] Naskah diterima: 16/4/2012 revisi: 2/5/2012 disetujui: 7/5/2012 Abstrak Keterlibatan Mahkamah Konstitusi RI dalam memeriksa dan memutus perkara impeachment Presiden secara tekstual merupakan kewajiban bukan kewenangan sehingga terjadi atau tidaknya impeachment Presiden dalam masa jabatannya akan ditentukan oleh kekuatan politik yang mendukung di sidang MPR. Seyogianya putusan yang diambil di sidang MPR didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi RI sebagai penafsir dan penegak konstitusi (constitusional court). Keadaan tersebut menyebabkan putusan Mahkamah Konstitusi menjadi dilematis karena akan ditentukan oleh kekuatan politik di sidang MPR. Selain hal tersebut, 3 (tiga) dari 9 (sembilan) hakim Mahkamah Konstitusi diajukan oleh Presiden dan 3 (tiga) lainnya dari DPR hal itu juga menjadi sangat dilematis. Kata Kunci : Impeachment, Mahkamah Konstitusi, Politik dan hukum. Dilematika Putusan Mahkamah Konstitusi Vs Kekuatan Politik dalam Impeachment Presiden Abstract The involvement of the constitutional court of RI in examining and ruling on the case of presidential impeachment is textually not the authority but obligation that whether or not presidential impeachment happen during president’s terms of office will be determined by the supporting political strength in the MPR session. The decision taken in the session should be based on the decision of Constitutional Court as the interpreter and the guardian of the constitution. This condition causes Constitutional Court decision becomes dillematic because it will be determined by the political strength in the session of the MPR. Besides,the fact that three of the nine judges are proposed by the President and three other are proposed by DPR is also dilemmatic. Keywords: Impeachment, Constitutional Court, Politics and law. PENDAHULUAN Runtuhnya rezim orde baru di bawah naungan kekuasaan Presiden Soeharto (alm) pada tanggal 21 Mei tahun 1998 adalah realita empiris bahwa sebaik apapun seorang pemimpin mengemas kekuasaan otoritarianisme dibalik legitimasi konstitusi dan hegemoni politik, hukum, kekuasaan birokrasi mulai unsur tertinggi sampai unsur terendah di daerah pada waktunya berakhir pula, sehingga memunculkan gagasan/ide pembaruan disegala bidang baik bidang politik, hukum, ekonomi, sosial dan tatanan pemerintahan yang jelas (tidak abuabu). Hal itu dapat disejajarkan dengan gerakan protes dari Paham Rasionalisme, Romantisme, dan Aufklarung yang didukung dan dipelopori oleh golongan menengah yang berkembang luas dan kemudian melahirkan revolusi politik dan sosial yang akhirnya memunculkan 2 (dua) revolusi di zaman modern, yakni revolusi Amerika Serikat Tahun 1776 dan Revolusi Perancis Tahun 1789 yang akhirnya menghasilkan paham demokrasi. Tahun 1999 merupakan tahun keemasan bagi masyarakat bangsa (civil society) Indonesia yang pro terhadap pembaruan. Bukti nyata keemasan itu ditandai dengan amandemen UUD 1945 telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dalam kurun waktu mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 dan menetapkan sistem pemerintahan presidensial versi Indonesia sebagai sistem pemerintahan negara hukum Indonesia. 334 Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012 Dilematika Putusan Mahkamah Konstitusi Vs Kekuatan Politik dalam Impeachment Presiden Amandemen terhadap UUD merupakan hal yang biasa dan wajar dilakukan dibanyak negara di dunia dalam rangka menyempurnakan sistem pemerintahan yang dianggap usang atau karena ada revolusi dan reformasi yang menghendaki perubahan besar dalam suatu negara yang akhirnya harus mengamandemen UUD dikarenakan UUD sebagai konstitusi negara merupakan pilar/pijakan pemerintah sebagai unsur pertama dan sumber utama Hukum Tata Negara serta sumber hukum secara umum yang mendasari kehidupan ketatanegaraan suatu Negara. Selain itu, UUD sebagai konstitusi dapat diaplikasikan secara komprehensif sebagai rule of the game dan rule of the moral dalam memecahkan konflik-konflik sosial dan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Dalam konteks Indonesia sebelum amandemen UUD 1945, Republik Kesatuan/ Kesatuan Republik Indonesia sama sekali tidak mengenal adanya lembaga impeachment hal itu juga dapat dilihat ketika BPUPKI sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, dan sidang kedua mulai tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945 tidak ada usulan tentang bagaimana mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden (impeachment) ketika Presiden dalam menjalankan pemerintahan Negara (menetapkan kebijakan) melanggar/menyimpang dari konstitusi (inkonstitusional), yang ada hanya perdebatan Ideologi dan dasar Indonesia Merdeka bahkan sampai Rancangan Hukum Dasar ditetapkan dan disahkan oleh PPKI 18 Agustus 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia sama sekali tidak dikenal adanya lembaga impeachment. Keadaan tersebut sepertinya memang sengaja dibiarkan oleh Moh. Yamin sebagai ahli hukum tata negara sekaligus anggota BPUPKI atau memang sebuah kekuarangan dalam UUD 1945 yang dirancang oleh para pendiri negara waktu itu. Bahkan, Harun Al-Rasyid mengatakan, bahwa UUD 1945 tidak mengenal lembaga ”impeachment”. karena ”impeachment” itu bahasa Inggris, tetapi baik menurut kamus bahasa Inggris maupun kamus-kamus hukum, ‘to impeach’ itu artinya memanggil atau mendakwa untuk meminta pertanggungjawaban dalam hubungan dengan kedudukan Kepala Negara atau Pemerintahan, “impeachment” berarti pemanggilan atau pendakwaan untuk meminta pertanggungjawaban atas persangkaan pelanggaran hukum yang dilakukannya dalam masa jabatan. Hampir semua konstitusi mengatur soal ini sebagai cara yang sah dan efektif untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap berada di jalur hukum dan konstitusi. Dalam sistem parlementer, selalu diatur adanya hak parlemen untuk mengajukan “mosi tidak percaya”, meskipun diimbangi pula dengan kewenangan pemerintah Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012 335 Dilematika Putusan Mahkamah Konstitusi Vs Kekuatan Politik dalam Impeachment Presiden untuk membubarkan parlemen menurut tata cara tertentu. Karena itu, masa kerja pemerintahan parlementer tidak ditentukan secara “fixed”. Sebaliknya, masa jabatan pemerintahan presidensil ditentukan secara ”fixed”, biasanya 4 (empat) sampai 7 (tujuh) tahun. Karena jangka waktunya cukup lama, maka sebagai pengimbang, kepada parlemen diberikan hak untuk meminta pertanggungjawaban di tengah jalan. Dengan begitu, negara yang mengidealkan prinsip supremasi hukum dapat terhindar dari kemungkinan dipimpin oleh seorang yang kemudian berubah menjadi ‘tiran’. Itu sebabnya, semua sistem kekuasaan memerlukan kontrol dan pengimbang. Satu lembaga dengan lembaga lain diatur berdasarkan prinsip “check and balance”. Kalau kinerja seorang pemimpin tidak bisa lagi diperbaiki, harus dimungkinkan untuk diganti dengan yang lebih baik. Namun demikian, semua konstitusi negara modern mengenal mekanisme pemberhentian atau penggantian pemimpinnya di tengah jalan. Yang berbeda hanya jenis pelanggaran hukum yang dijadikan alasan untuk pendakwaan. Pelanggaran hukum yang dijadikan alasan itu ada yang bersifat pidana dan ada juga yang bersifat tata negara. Konstitusi Amerika Serikat Pasal 2 ayat (4) (treason, bribery or other high crimes, and misdemeanors), Konstitusi Argentina Pasal 52 (malfeasance or crime committed in exercise of their offices or for common crimes), Konstitusi Perancis Pasal 68 (only the case of high treason), dan Konstitusi Rusia Pasal 93 ayat (1) (treason or the commission of some other grave crime), misalnya, mengaitkannya dengan pelanggaran hukum pidana. Tetapi Konstitusi Jerman (Pasal 61 ayat 1) mengaitkan impeachment itu, baik dengan pelanggaran tata negara maupun pidana, dan bahkan dengan semua bidang hukum: “The Bundestag or the Bundesrat may impeach the Federal President before the Federal Constitusional Court for wilful violation of this Basic Law or any other federal statute”. Presiden dapat di’impeach’, baik karena didakwa melanggar UUD ataupun undang-undang Federal lainnya.1 Selain itu, menurut Jimly Asshiddiqie 2, dalam beberapa literatur lain istilah impeachment berasal dari kata “to impeach”, yang berarti meminta pertanggungjawaban. Jika tuntutannya terbukti, maka hukumannya adalah “removal from office”, atau pemberhentian dari jabatan. Dengan kata lain, kata “impeachment” itu sendiri bukanlah pemberhentian, tetapi baru bersifat penuntutan atas dasar pelanggaran hukum yang dilakukan. Oleh karena itu, dikatakan Charles L. Black, “Strictly speaking, ‘impeachment’ means ‘accusating’ or ‘charge’.” Artinya, 1 2 Jimly Asshiddiqie, “Impeachment”, dalam legalitas.org.html, Juli 2009, diunduh September 2009. Jimly Asshiddiqie, 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, h. 600 336 Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012 Dilematika Putusan Mahkamah Konstitusi Vs Kekuatan Politik dalam Impeachment Presiden kata impeachment itu dalam bahasa Indonesia dapat kita alih bahasakan sebagai dakwaan atau tuduhan. Menurut Black Law Dictionary impeachment adalah :3 A criminal proceeding against a public officer. Before a quasi political court, instituted by a written accusation called “article of impeachment”. For example a written accusation by the house of representatives of the United States to the Senate of the United States, against the President, Vice President, or an officer of the United States. Secara teks tual yuridis konstitusional impeachment (dakwaan/ tuduhan/pemakzulan) terhadap Presiden dan/atau wakil Presiden dalam teks dan konteks negara Indonesia baru ditemukan setelah amandemen ke III yang ditetapkan tanggal 9 November 2001 sebagaimana Pasal 7A dan 7B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana jika diamati Pasal 7A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai parameter pokok dapat tidaknya seorang Presiden dan/atau wakil Presiden di-impeach dalam masa jabatannya sebagai berikut : ”Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”. Pemetaan dari rumusan Pasal 7A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, adalah : 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat dapat memberhentikan Presiden dan/atau wakil Presiden dalam masa jabatannya. 2. Untuk memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya harus ada bukti pelanggaran hukum, berupa : a. Pengkhianatan terhadap negara b. Korupsi c. Penyuapan d. Tindak pidana berat lainnya e. Perbuatan tercela 3 Kunthi Dyah Wardani, 2007, Impeachment Dalam Ketatanegaraan Indonesia, Yogyakarta: UII Press, h.16 Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012 337 Dilematika Putusan Mahkamah Konstitusi Vs Kekuatan Politik dalam Impeachment Presiden f. Terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden Untuk memutuskan Presiden dan/atau wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum perlu adanya pembuktian yang independen oleh lembaga peradilan. Oleh karena itu, adanya Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengawal dan sekaligus penafsir konstitusi merupakan pintu pertama impeachment Presiden dan/atau wakil Presiden. (Vide Pasal 7B ayat (1) dan Pasal 24C ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945). Jika memperhatikan article II Section 4 (Pasal II bagian 4) konstitusi Amerika menegaskan bahwa : ”Presiden, Wakil Presiden dan semua pegawai sipil Amerika Serikat, akan diberhentikan dari jabatannya apabila kena tuntutan pertanggungjawaban karena, dan dinyatakan bersalah, dalam hal pengkhianatan, penyuapan atau kejahatan-kejahatan besar lainnya dan pelanggaran-pelanggaran” Secara historis, impeachment terjadi di Amerika Serikat sebanyak 3 (tiga) kali dengan motif yang berbeda-beda. Pada tahun 1868 terjadi impeachment terhadap Presiden Andrew Johnson. Dalam kasus tersebut, mayoritas anggota parlemen Amerika Serikat setuju untuk melakukan impeachment terhadap Presiden Andrew Johnson karena telah melakukan pelanggaran sumpah jabatan dan dinyatakan ketentuan konstitusi Amerika Serikat yang disahkan pada tanggal 2 Maret 1867. Presiden Andrew Johnson telah memberhentikan Edwin M. Stanton sebagai Sekretaris Departemen Pertahanan dan menggantinya dengan pejabat yang lain tanpa persetujuan Senat, di mana undang-undang tersebut jelas mengharuskan adanya persetujuan Senat. Selain itu, juga dituduh melanggar undang-undang Federal Amerika Serikat, yaitu memberikan perintah kepada William H. Emory yang seharusnya melalui Jenderal Angkatan Darat. Namun pada proses ditingkat Senat kedua tuduhan tersebut dibebaskan dan Presiden Andrew Johnson tidak diberhentikan dari jabatannya karena ada perbedaan satu suara anggota Senat sehingga memenangkan Presiden Andrew Johnson. Selain kasus Andrew Johnson, pada 1974, Presiden Richard M. Nixon dituduh melakukan pelanggaran sumpah jabatan; melakukan tindakan yang melanggar hak-hak konstitusional warga negara; pelanggaran terhadap hukum yang 338 Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012 Dilematika Putusan Mahkamah Konstitusi Vs Kekuatan Politik dalam Impeachment Presiden berlaku dibidang pemerintahan; dan lalai menghormati panggilan dari Komite Kehakiman. Dalam proses ditingkat Komite Kehakiman disimpulkan bahwa tindakan yang dapat berakibat pada impeachment tidak harus merupakan tindak pidana yang dapat didakwakan. Impeachment terhadap Presiden Richard M. Nixon didasarkan pada tuduhan antara lain: menghambat peradilan, penyalahgunaan kekuasaan, penghinaan terhadap kongres. Soimin dalam bukunya menyebutkan bahwa tuduhan tersebut berkaitan erat dengan skandal Watergate yang terjadi pada tanggal 17 Juni 1972, yaitu masuknya secara tidak sah beberapa orang di kantor pusat Komite Nasional Demokrat di Watergate, Washington DC dan melakukan penyadapan telepon, sehingga akhirnya proses penyelidikan untuk melakukan impeachment terhadap Presiden Richard M. Nixon harus segera dilakukan oleh Kongres. Namun demikian, sebelum proses pengambilan putusan berlangsung, Presiden Richard M. Nixon mengundurkan diri dari jabatan Presiden Amerika Serikat setelah parlemen menyetujui beberapa pasal impeachment terhadap Presiden Richard M. Nixon. Oleh karena itu, pengunduran diri yang dilakukan Presiden Richard menyebabkan gugurnya proses impeachment.4 Kemudian impeachment selanjutnya terjadi pada Presiden William Jefferson Clinton didasarkan pada 4 (empat) tuduhan hasil keputusan Komite Kehakiman berupa: melakukan sumpah palsu di hadapan juri; melakukan sumpah palsu dalam perkara kasus pelecehan seksual kepada Monica Leswinsky; menghambat peradilan; memberikan respons yang tidak layak atas pernyataan tertulis dari Komite Kehakiman.5 Karenanya, selama 200 (dua ratus) tahun di Amerika Serikat hanya 13 pejabat yang terkena tuntutan itu: 9 (sembilan) hakim, seorang hakim Mahkamah Agung, seorang Menteri Pertahanan, seorang Senator, dan seorang Presiden, Andrew Johnson. Dalam kasus Presiden Nixon, meskipun parlemen telah memprakarsai adanya impeachment, namun Presiden telah mengundurkan diri sebelum diadakan pemungutan suara. Dari 13 (tiga belas) kasus tersebut, hanya 4 (empat) hakim yang dinyatakan bersalah dan dipecat dari jabatannya. Dalam hal demikian, pejabat negara bagian dapat juga dikenai impeachment oleh badan legislatif negara bagian masing-masing.6 4 5 6 Soimin, 2009, Impeachment Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, Yogyakarta: UII Press, h. 67-68 Hamdan Zoelva, 2005, Impeachment Presiden: Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945, Jakarta: Konstitusi Press, h. 110-111 Richard C. Schroeder, tanpa tahun, Garis Besar Pemeritahan Amerika, AS: Dinas Penerangan AS, h. 7 Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012 339 Dilematika Putusan Mahkamah Konstitusi Vs Kekuatan Politik dalam Impeachment Presiden Sementara itu, di Korea Selatan pada tanggal 12 Maret 2004, terjadi proses impeachment, yaitu Majelis Nasional memungut suara 193 (seratus sembilan puluh tiga) setuju lawan 2 (dua) menolak, terhadap penghentian sementara kekuasaan Presiden Roh Moo Hyun atas pembuktian bahwa dia menerima sumbangan tidak tercatat dari konglomorat Korea yang ingin mencari kesempatan usaha dari pemerintah, dan yang kedua adalah karena Roh mencuri start kampanye Presiden. Meskipun demikian hasil survei rakyat Korea menyatakan 70% (tujuh puluh perseratus) rakyat merasakan seharusnya Presiden Roh tidak perlu diimpeach, namun rakyat juga mengatakan bahwa sebagai pemimpin Negara dia tidak memberi suri teladan yang baik kepada bangsa Korea. Sejak voting di Majelis Nasional, pemerintahan sementara dipegang oleh Perdana Menteri. Proses impeachment berlanjut di Mahkamah Konstitusi Korea Selatan pada tanggal 14 April 2004 membatalkan hasil voting Majelis Nasional dan Presiden Roh kembali menduduki kursi Presiden Korea Selatan sampai berakhir 2008. Hasil dari proses pendewasaan demokrasi ini selanjutnya adalah pembersihan besar dari bisnis konglomerat yang menggurita di pemerintahan Korea Selatan.7 Kemudian di Filipina Selatan Di Filipina tahun 2000 juga terjadi impeachment ketika Presiden Joseph Estrada didakwa menerima bayaran milyiran Peso sewaktu Gubernur Negara bagian Illocos Sur bersaksi bahwa itu adalah uang setoran permainan judi lokal dan setoran atas penyelidikan kasus tembakau yang pernah terjadi sebelumnya. Tanggal 13 November 2000, Ketua Parlemen membentuk Komisi Sidang impeachment kepada Senat, yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung Hilario Davide Jr. Dalam tayangan siaran langsung di radio dan televisi, persidangan yang memanggil para saksi dan bukti-bukti sangat menguatkan kebenaran dakwaan terhadap Presiden Joseph Estrada. Tanggal 16 Januari 2001, pada persidangan itu, Dewan Juri yang berjumlah 11 dari 21 orang memutuskan menolak membuka amplop yang berisi bukti-bukti kuat keterlibatan Presiden dalam korupsi dan penyuapan dan lalu sidang menjadi buntu, dan seketika gelombang protes seluruh Filipina menggoncang bangsa. Tiga hari kemudian, tanggal 19 Januari 2001, Panglima Militer Filipina Jenderal Angelo Reyes, mengambil sikap, yaitu berpihak kepada Wakil Presiden Gloria Macapagal Arroyo secara penuh, dan Mahkamah Agung lalu membuat Fatwa bahwa kursi Kepresidenan kosong meskipun Joseph Estrada tidak mundur dari jabatan. Siang itu juga Wakil Presiden 7 Cahyo Baroto, “Belajar dari Impeachment Beberapa Negara Lain”, http://news.okezone.com/read/2010/03/08/58/310152, diunduh 8 Maret 2010. 340 Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012 Dilematika Putusan Mahkamah Konstitusi Vs Kekuatan Politik dalam Impeachment Presiden diangkat sumpahnya menjadi Presiden Filipina yang baru. Hasilnya adalah situasi politik yang sempat memanas, dan memuncak dengan perlawanan Presiden Joseph Estrada, menjadi cepat pulih dan stabil setelah militer mengambil posisi berpihak kepada kebenaran dan berani bersikap dengan jelas demi pulihnya kestabilan dan kedamaian tanpa harus mengeluarkan sebutir pelurupun.8 PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN IMPEACHMENT DI INDONESIA Sejarah impeachment (pemberhentian) Presiden di Indonesia itu sendiri pernah terjadi selama 2 (dua) kali impeachment (pemberhentian) presiden dalam masa jabatannya dengan kekuatan politik MPR waktu itu: Pertama, pada tahun 1966, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) menarik mandat Presiden Soekarno. Dalam TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno disebutkan, bahwa Presiden Soekarno diganti oleh Jendral Soeharto, dengan pertimbangan bahwa Presiden Soekarno tidak dapat melakukan kewajibannya dan tidak dapat melaksanakan haluan negara sebagaimana ditetapkan oleh UndangUndang Dasar dan MPRS. Sebelum amandemen UUD 1945 impeachment Presiden tidak diatur di dalam konstitusi negara, akan tetapi hanya sedikit dalam penjelasan UUD 1945 yang merupakan bagian tak terpisahkan. Dalam Pasal 8 UUD 1945 menegaskan, bahwa ”jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya”. Pasal tersebut di atas, tidak mengatur tentang pemberhentian Presiden, hanya mengatur mengenai “penggantian” Presiden. Jika Presiden meninggal dunia ia dapat diganti karena mangkat. Jika Presiden berhenti secara sepihak seperti yang dilakukan Presiden Soeharto (mengundurkan diri), maka ia dapat diganti karena menyatakan diri berhenti. Jika ia mengajukan permintaan berhenti atau mengajukan mengundurkan diri kepada MPR, maka MPR harus melakukan tindakan yang bernama penggantian, bukan pemberhentian. Karenanya TAP No. XXXIII/MPRS/1967 menetapkan Presiden Soekarno diganti oleh Jenderal Soeharto berdasarkan ketentuan Pasal 8 UUD 1945 karena pertimbangan bahwa Presiden 8 Ibid. Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012 341 Dilematika Putusan Mahkamah Konstitusi Vs Kekuatan Politik dalam Impeachment Presiden Soekarno tidak dapat melakukan kewajibannya, tidak dapat melaksanakan GarisGaris Besar Haluan Negara sebagaimana ditetapkan oleh UUD dan MPRS. Presiden Soekarno bukan diberhentikan, melainkan diganti dengan Soeharto sebagai Pejabat Presiden. Dengan logika demikian, berarti Pasal 8 itu menentukan bahwa apabila Presiden dinilai oleh MPR tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya, maka ia dapat diganti di tengah jalan. Alasan untuk mengganti Presiden tidak perlu karena terjadinya pelanggaran sebelumnya oleh Presiden. Meskipun Sidang Istimewa MPRS 1967 diadakan karena adanya memorandum DPRGR dan ditolaknya laporan pertanggungjawaban Presiden, baik Nawaksara maupun pelengkapnya Nawaksara. Karenanya dalam Pasal 4 TAP No. XXXIII/MPRS/1967 ditegaskan bahwa menetapkan berlakunya TAP MPRS No. XV/MPRS/1966, dan mengangkat Jenderal Suharto, pengemban TAP MPRS No. IX/MPRS/1966 sebagai pejabat Presiden berdasarkan Pasal 8 UUD 1945 hingga dipilihnya Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilihan umum. Kedua, terjadi pada Sidang Istimewa yang digelar pada bulan Agustus tahun 2001. Ketika itu MPR juga telah mencabut mandat atau memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid (alm) dengan alasan bahwa presiden dinyatakan telah melanggar Haluan Negara, karena tidak hadir dan menolak untuk memberi pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa MPR, serta penerbitan Maklumat tanggal 23 Juli 2001 yang dianggap inkonstitusional oleh MPR. Kesemuanya itu bermuara pada impeachment (pemberhentian) Presiden dari jabatannya sebagai kepala negara dan pemerintahan. Pengusulan impeachment presiden yang dilakukan oleh DPR kepada MPR melalui Mahkamah Konstitusi RI adalah sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja Presiden sebagai kepala eksekutif di mana menurut Pasal 69 UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetuan bersama. Sementara fungsi anggaran diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Sedangkan fungsi pengawasan diwujudkan untuk melakukan pengawasan 342 Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012 Dilematika Putusan Mahkamah Konstitusi Vs Kekuatan Politik dalam Impeachment Presiden terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, dan Peraturan Pelaksanaannya. ANTARA HUKUM DAN POLITIK DALAM IMPEACHMENT PRESIDEN Salah satu prinsip yang ada dalam pemerintahan modern adalah adanya pertanggungjawaban. Kekuasaan pemerintahan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab karena kekuasaan itu lahir dari suatu kepercayaan rakyat. Kekuasaan yang diperoleh dari suatu lembaga yang dibentuk secara demokratis adalah logis harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Dengan demikian pertanggungjawaban merupakan syarat mutlak yang harus ada pada pemerintahan demokrasi. Di negara demokrasi tidak satupun kekuasaan yang tidak perlu pertanggungjawaban. Doktrin ini hanya berlaku untuk kekuasaan dalam arti real power yang dilaksanakan oleh Presiden selaku kepala eksekutif. Kekuasaan Kepala Negara yang not a real power tidak perlu dipertanggungjawabkan. Presiden yang bertanggung jawab dalam negara Republik secara politis mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepada pemilik kedaulatan.9 Model pertanggungjawaban yang dianut oleh TAP No. III/1978 berbeda dengan mekanisme impeachment yang dikenal di beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan Philipina sebagaimana uraian di awal. Perbedaan mendasar antara mekanisme pertanggungjawaban Presiden dalam TAP No. III/1978 dengan impeachment kedua negara tersebut adalah dari segi substansinya. Kedua negara tersebut menerapkan sistem Presidensil secara konsekuen, sehingga Presiden tidak dapat dijatuhkan di tengah masa jabatannya, kecuali ia telah melanggar konstitusi dan hukum positif negara tersebut. Pada dasarnya mekanisme impeachment merupakan suatu prosedur istimewa yang mengatasi stabilnya posisi Presiden dalam sistem presidensil. Karena kepala pemerintahannya tidak dapat dijatuhkan dengan mosi tidak percaya Parlemen sebagaimana dalam sistem Parlementer. Ada prinsip dalam Negara hukum yang biasa dikenal dengan equality be fore the law (kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi penyelenggara Negara, pejabat Negara dan bagi masyarakat biasa. Prinsip tersebut tidak dapat ditawar lagi oleh pihak penyelenggara negara karena merupakan salah satu model penyelenggaraan Negara hukum modern. 9 Bonny dan Novan, “Penolakan pertanggungjawaban Presiden Sebagai Mandataris MPR”, Majalah Hukum dan kemasyarakatan, Jakarta, 1991, h.1, dalam Mirza Nasution, “Beberapa Masalah Tentang Pemberhentian Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Kuasi Presidensial Di Indonesia” Fakultas Hukum Bagian Ilmu Tatanegara Universitas Sumatera Utara Tanpa Tahun, h. 1 Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012 343 Dilematika Putusan Mahkamah Konstitusi Vs Kekuatan Politik dalam Impeachment Presiden Pengusulan impeachment Presiden oleh DPR kepada MPR tidak dapat dilakukan secara politis sebagaimana pemberhentian Presiden pada Soekarno dan Abdurrahman Wahid. Namun terlebih dahulu harus diajukan kapada Mahkamah Konstitusi RI sebagai pintu pertama untuk diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan pendapat DPR, bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, perbuatan tercela dan tindak pidana berat lainnya. Sebagaimana Pasal 24C ayat (2) Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Keterlibatan Mahkamah Konstitusi RI dalam impeachment Presiden adalah merupakan domain politik hukum amandemen UUD 1945 sebagaimana Pasal 7A dan 7B UUD RI Tahun 1945 di mana ada kemungkinan tolak tarik antara supremasi hukum dan supremasi politik di DPR-MPR untuk memakzulkan Presiden atau tidak dalam masa jabatannya dan legalitas putusan Mahkamah Konstitusi RI untuk menentukan terbukti atau tidaknya Presiden melakukan pelanggaran hukum sebagaimana Pasal 7A UUD RI Tahun 1945 berupa: pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dipurbasangkakan oleh DPR. Hanya dalam kasus demikian terlebih dahulu diajukan ke Mahkamah Konstitusi RI sebagai pintu pertama dalam proses impeachment secara yuridis konstitusional. Dalam proses impeachment Presiden antara supremasi hukum dan supremasi politik terjadi tolak tarik yang kuat, karenanya Mahfud MD mengemukakan, bahwa dalam realita empiris hukum lahir sebagai refleksi dari konfigurasi politik yang melatarbelakanginya. Kalimat-kalimat yang ada dalam aturan hukum tidak lain merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaingan. Dalam kenyataan terlihat bahwa politik sangat menentukan bekerjanya hukum.10 Dalam kalangan ahli hukum minimal ada 2 (dua) pandangan mengenai hubungan kausalitas antara politik dan hukum. Kaum idealis yang lebih bediri pada sudut das sollen mengatakan bahwa hukum harus mampu mengendalikan 10 Moh. Mahfud MD, 1999, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Yogyakarta: Gama Media, h. 69 344 Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012 Dilematika Putusan Mahkamah Konstitusi Vs Kekuatan Politik dalam Impeachment Presiden dan merekayasa perkembangan masyarakat, termasuk dalalm kehidupan masyarakatnya. Penulis seperti Roscoe Pound telah lama berbicara tentang “law as a tool of social engineering”.11 Akan tetapi kaum realis seperti Von Savigny mengatakan bahwa hukum selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Ini berarti bahwa hukum mau tidak mau menjadi independent variable atas keadaan di luarnya, terutama keadaan politiknya.12 Satjipto Rahardjo mengemukakan, bahwa kalau kita melihat hubungan antara sub sistem politik dengan sub sistem hukum, maka tampak bahwa politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar, sehingga hukum selalu berada dalam posisi yang lemah.13 Karenanya Sri Soemantri sering mengeluh bahwa perjalanan politik dan hukum di Indonesia ini ibarat perjalanan kereta api di luar relnya. Artinya banyak sekali praktek politik yang secara substantif bertentangan dengan aturan hukum.14 (keluar dari aturan hukum yang telah ditentukan). Hal itu menurut Mahfud dimaksudkan untuk menegaskan bahwa di dalam kenyataan empirik politik sangat menentukan bekerjanya hukum. Pengaruh politik terhadap hukum dapat berlaku terhadap penegakan hukumnya dan karakteristik produk-produk hukum serta proses pembuatannya.15 Demikian halnya dalam konteks impeachment Presiden, di mana setelah Mahkamah Konstitusi RI memeriksa dan memutuskan bahwa Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana Pasal 7A UUD RI Tahun 1945 amandemen, berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden di mana usul permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi RI hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Jika Mahkamah Konstitusi RI memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi 11 12 13 14 15 Ibid., h. 70-71 Ibid. Satjipto Rahardjo, 1985, Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antar Disiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional, Bandung: Sinar Baru, h.71 Ibid. Ibid., h.72 Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012 345 Dilematika Putusan Mahkamah Konstitusi Vs Kekuatan Politik dalam Impeachment Presiden syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/ atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka di situ terjadi pertentangan kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi RI dan kekuatan politik yang akan meneruskan putusan Mahkamah Konstitusi RI atau menolak putusan Mahkamah Konstitusi RI setelah MPR mendengar penjelasan Presiden. Meskipun Mahkamah Konstitusi RI memutuskan bahwa Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, atau tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum, namun kehendak politik begitu kuat untuk memberhentikan atau tidak memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya, maka hal itu juga akan ditentukan oleh kekuatan politik yang menyertai terjadinya impeachment, bukan ditentukan oleh putusan Mahkamah Konstitusi RI, di sisi lain jika MPR mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi RI baik terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum, maka MPR sudah mengabaikan penegakan konstitusi disini pula putusan Mahkamah Konstitusi delimatis. Dalam keadaan demikian, kekuatan politik suprem. Karena ketika keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang harus diambil dalam sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak mencapai kourum tersebut, maka tidak akan terjadi pemberhentian meskipun Mahkamah Konstitusi RI memutuskan Presiden dan/atau Wakil Presiden telah terbukti melakukan pelanggaran hukum seagaimana Pasal 7A UUD Negara RI Tahun 1945, akan tetapi jika mencapai kourum, maka akan terjadi pemberhentian Presiden. Oleh 346 Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012 Dilematika Putusan Mahkamah Konstitusi Vs Kekuatan Politik dalam Impeachment Presiden karena itu, jika MPR menolak atau mengingkari putusan Mahkamah Konstitusi RI yang menyatakan bahwa Presiden telah terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7A UUD RI Tahun 1945, berarti MPR menjalankan fungsi legislatif yang di dalamnya terdapat fungsi kontrol/ pengawasan, akan tetapi jika MPR menerima putusan Mahkamah Konstitusi RI, maka MPR menjalankan fungsi yudisial, yakni menjalankan apa yang telah diputusan oleh lembaga peradilan kontsitusi dalam menegakkan konstitusi (constitusional court). Saat ini di Indonesia hanya Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independen untuk menyelenggarakan peradilan konstitusi guna menegakkan hukum dan keadilan secara yuridis konstitusional yang akan menentukan apakah Presiden dan atau wakil presiden benar-benar telah melanggar hukum atau tidak. Namun demikian, berhenti atau tidaknya Presiden dan/atau wakil Presiden dalam masa jabatannya tergantung kehendak politik lebih-lebih jika anggota MPR-DPR mayoritas pemenang Pemilu dan sebagai pendukung Presiden terpilih. Abdul Latif mengemukakan, bahwa keterlibatan Mahkamah Konstitusi RI dalam proses impeachment hanya sebatas kewajiban bukan kewenangan. Dikatakan kewajiban karena putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam hal ini tidak final atau dapat dianulir oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini suatu indikasi masih adanya supremasi politik terhadap hukum. Akibatanya bukan tidak mungkin keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk terjadinya impeach Presiden hanya didasarkan pertimbangan politik. Jika hal ini yang terjadi, maka impian mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan konstitusional sulit terwujud. Idealnya, putusan yang diambil Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam impeach Presiden hanya didasarkan pada pertimbangan hukum mengingat presiden sudah dipilih secara langsung dalam pemilihan umum presiden, sehingga rakyatlah yang berhak impeach. Di samping itu, konsepsi Pasal-Pasal yang mengatur impeachment sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ternyata tidak singkron alias rancu, karena wewenang dan kewajiban yang dimiliki Mahkamah Konstitusi RI kurang dapat dijadikan untuk mewujudkan rechtsidee secara maksimal, khususnya cita-cita membangun satu tatanan masyarakat dan pemerintahan yang demokratis dan mandiri berdasarkan hukum.16 16 Abdul Latif, 2007, Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokratis, Yogyakarta: CV. Kreasi Total Media, h. 216-217 Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012 347 Dilematika Putusan Mahkamah Konstitusi Vs Kekuatan Politik dalam Impeachment Presiden Ada sebuah skenario besar yang sengaja dibuat oleh para perancang amandemen UUD 1945, yakni keterlibatan Mahkamah Konstitusi RI dalam impeachment Presiden yang bukan merupakan kewenangannya melainkan sebatas kewajiban untuk memeriksa dan memutus pelanggaran hukum berupa: pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Mestinya kewajiban untuk memeriksa dan memutus peristiwa impeachment presiden ini dimaksukkan dalam kewenangannya yang bersifat final agar tidak terjadi tawar-menawar kekuasaan politik, di sinilah hukum dengan kekuasaan berinterakasi dengan kekuatan masing-masing. Dalam kaitan ini, pandangan tentang hubungan hukum dan kekuasaan tidaklah tunggal. Antara kaum idealis yang berorientasi das sollen dan kaum empiris yang melihat hukum sebagai das sein, memberikan pandangan yang berbeda. Namun kedua pandangan itu, mempunyai pendapat yang sama bahwa seharusnya hukum itu suprem atas kekuasaan. Ada 2 (dua) fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat, yaitu pertama sebagai sarana kontrol sosial dan kedua sebagai sarana untuk melakukan ”social engineering”. Sebagai sarana kontrol sosial maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat berada di dalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya.17 Di dalam peranannya yang demikian ini hukum hanya mempertahankan saja apa yang telah menjadi sesuatu yang tetap dan diterima di dalam masyarakat atau hukum sebagai penjaga status quo. Tetapi ketika melihat teori dari Roscoe Pound yang menyatakan bahwa “law as tool of social engineering” maka akan melihat bahwa hukum harus mempengaruhi kehidupan masyarakat.18 Tetapi manakala mengacu pada teori Von Savigny yang mengatakan bahwa “hukum berubah manakala masyarakat berubah”, maka yang dimaksudkan adalah bahwa hukum harus mampu mengikuti perkembangan dan memenuhi tuntutan masyarakat. Sebenarnya implisit di dalamnya bahwa hukum dipengaruhi oleh kekuatankekuatan eksternal, termasuk subsistem politiknya. Realita empirik di lapangan menunjukkan bahwa betapa sering kali hukum tidak mempunyai otonomi yang kuat, karena energinya lebih lemah daripada energi subsistem politiknya. Sehingga yang dapat dilihat bukan saja materi hukum itu yang sarat dengan konfigurasi kekuasaan, melainkan juga penegakannya kerap 17 18 Soerjono Soekanto, 1973, Pengantar Sosiologi Hukum, Jakarta: Rajawali Press, h. 58 Roscoe Pound, 1972, Pengantar Filsafat Hukum, Terjemahan Mohammad Radjab, Jakarta: Bhratara, h.7 348 Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012 Dilematika Putusan Mahkamah Konstitusi Vs Kekuatan Politik dalam Impeachment Presiden kali diintervensi oleh kekuasaan, sehingga hukum sebagai petunjuk menjadi terabaikan. Dari kenyataan empirik yang seperti itulah kemudian muncul teori “hukum sebagai produk kekuasaan (politik)”.19 Karenanya menurut hemat penulis bahwa hukum itu kekuasaan dan kekuasaan itu adalah hukum. Hukum dapat menciptakan kekuasaan dan kekuasaan dapat menciptakan hukum.20 meskipun ada yang menyebut recht is recht mach is mach. Satjipto Rahardjo mengemukakan bagi orang yang melakukan telaah tentang hukum dan kekuasaan, minimal akan menemukan dua pandangan yaitu : pertama, hukum menentukan dan mempengaruhi kekuasaan; kedua, hukum dipengaruhi oleh kekuasaan. Idealnya memang antara hukum dan kekuasaan paling tidak saling mendukung. Dalam arti hukum harus ditegakkan dengan kekuasaan, agar daya paksanya bisa efektif. Sebaliknya kekuasaan harus dijalankan dengan prinsip-prinsip hukum, agar tidak sewenang-wenang. Dalam konteks inilah kita bisa memahami pernyataan, bahwa “hukum tanpa kekuasaan adalah anganangan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Dengan pengutaraan ini, kita melihat dengan jelas persoalan yang kita hadapi, yaitu hubungan antara hukum dan kekuasaan.21 Secara prosedural, desain hukum menjadi kental bermuatan politik. Hal ini dapat dimengerti karena sistem hukum memang tidak mungkin menutup diri dari sistem-sistem lain. Bahkan, pernyataan John Austin tentang sistem hukum tertutup pada dasarnya mengalami contradictio in terminis dengan pernyataannya semula tentang law as a command of lawgivers. Keterkaitan sistem hukum dengan sistem lain ditunjukkan secara sangat baik oleh Talcott Parson dengan Teori Sibernetika-nya22. Dalam teorinya, Parson menyebutkan tentang ada 4 (empat) subsistem: ekonomi, politik, sosial dan budaya yang senantiasa melingkari kehidupan kemasyarakatan. Dilihat dari arus energi, subsistem ekonomi menempati kedudukan paling kuat, diikuti subsistem politik, baru kemudian subsistem sosial (di mana hukum ada di dalamnya), dan diakhiri oleh subsistem budaya. Di sisi lain, dilihat dari arus informasi (tata nilai), subsistem budaya justru yang paling kaya, diikuti oleh subsistem sosial, subsistem politik, dan berakhir pada subsistem ekonomi. 19 20 21 22 Moh. Mahfud, MD., 1999, Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi, Yogyakarta: Liberty, h. 272 Nadir, “Memformat Equity and Equality Antara DPR dan DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Publika FIA Unira Pamekasan, Tahun I No. I, Januari, 2010, h. 48 Satjipto Rahardjo, 1996, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 146 Satjipto Rahardjo, Beberapa Pemikiran……………Op.Cit. Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012 349 Dilematika Putusan Mahkamah Konstitusi Vs Kekuatan Politik dalam Impeachment Presiden Apa maksudnya penjelasan Parson di atas, di sini terlihat bahwa anggapan bahwa hukum adalah produk politik sesungguhnya hanya dapat dibenarkan apabila dilihat dari arus energi saja sebagai lembaga pembentuk (DPR). Sementara jika dilihat dari aspek informasi (material), hukum adalah produk budaya. Oleh karena itu, diskursus aliran-aliran filsafat hukum dan teori hukum seperti yang dikemukakan di atas, menjadi makin relevan apabila dikaji dari perspektif parsonian. Sekalipun pandangan bahwa hukum adalah produk politik itu sangat sepihak, tidak terbantahkan bahwa pengaruh politik memang besar terhadap pengembanan hukum (rechtsbeoefening) khususnya di Indonesia. Keadaan politik tertentu dapat mempengaruhi produk hukum, seperti mengenai impeachment Presiden bahwa produk hukum putusan Mahkamah Konstitusi RI yang menyatakan presiden terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum dapat dikalahkan oleh produk lembaga yang berpolitik (MPR) yang nantinya setelah mendengar penjelasan Presiden dalam sidang paripurna MPR, MPR dapat menetapkan dan memutuskan bahwa Presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum karena mekasnisme yang digunakan mekanisme politik, akhirnya putusan Mahkamah Konstitusi RI menjadi sia-sia sebab untuk apa Presiden diajukan dan diusulkan ke Mahkamah Konstitusi RI untuk diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi RI, jika putusan Mahkamah Konstitusi RI akhirnya diabaikan. Karenanya bahwa kekuatan politik dalam percaturan perpolitikan dibanding hukum di Indonesia sangat kuat dan dapat menentukan dapat tidaknya impeach Presiden dalam masa jabatannya termasuk dalam mengatur tercapai tidaknya kourum sidang MPR. DILEMATIKA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS IMPEACHMENT PRESIDEN Peran Mahkamah Konstitusi RI di sini jelas adalah interaksinya antara hukum dengan kekuasaan politik di satu sisi yang menekan kewajibannya dalam rangka menegakkan hukum, tetapi di sisi lain kekuasaan begitu dominannya sehingga putusan hukum lembaga peradilan konstitusi (constitusional court) harus ditawar dengan kekuasaan Presiden dan kekuatan politik. Keadaan demikian, posisi Presiden menjadi semakin kuat, karena interpretasi atau penafsiran atau penentuan apakah presiden dan/atau wakil Presiden melanggar hukum, akan bergantung kepada putusan Mahkamah konstitusi dengan 350 Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012 Dilematika Putusan Mahkamah Konstitusi Vs Kekuatan Politik dalam Impeachment Presiden jumlah anggota 9 (sembilan) orang hakim, yang 3 (tiga) di antaranya diajukan oleh Presiden. Jadi secara politik, Presiden telah memegang 3 (tiga) suara di Mahkamah Konstitusi. Berarti jika putusan Mahkamah Konstitusi dijalankan berdasarkan voting, yaitu tidak ada kesepakan bulat di antara semua anggota hakim Mahkamah Konstitusi, maka Presiden tinggal mencari dukungan suara 2 (dua) orang lagi karena 3 (tiga) hakim konstitusi tersebut secara politik pernah berhutang budi pada Presiden, karenanya netralitas hakim dipertanyakan. Presiden tidaklah sulit untuk mendapat dukungan suara dari 3 (tiga) orang anggota hakim Mahkamah Konstitusi yang pernah diajukan. Secara politik, mempengaruhi 3 orang lebih mudah dibandingkan dengan harus mempengaruhi 50% (lima puluh perseratus tambah satu) dari seluruh anggota MPR. Ketentuan ini yang akan dapat menyelamatkan apabila Presiden dituduh oleh DPR telah melanggar hukum. Karena disitu, tuduhan DPR tersebut dapat saja ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Jika oleh Mahkamah Konstitusi, Presiden dan/atau wakil presiden diputus tidak melakukan pelanggaran hukum yang dituduhkan itu, maka MPR tidak berwenang memberhentikan Presiden. Jadi, penentu pertama dan sangat dominan apakah Presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan oleh MPR adalah Mahkamah Konstitusi. Problematika yang timbul dari Pasal 7A dan 7B UUD RI Tahun 1945, jika Mahkamah Konstitusi memutuskan Presiden dan/atau wakil presiden melanggar hukum, namun MPR ternyata tidak memberhentikan Presiden dan/ atau wakil presiden. Kasus demikian kemungkinan bisa saja terjadi, mengingat MPR adalah lembaga politik, dan dalam pengambilan keputusan dapat berdasarkan suara terbanyak, bukan berdasarkan objektifitas hukum. Namun demikian, di sisi lain, posisi Presiden semakin kuat, karena ia tidak akan mudah dijatuhkan atau diberhentikan oleh MPR, meskipun ia berada dalam kondisi berbeda pandangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan parlemen baik kepada DPR maupun kepada DPD. Selama tidak diputus melanggar hukum oleh Mahkamah Konstitusi, maka posisi presiden akan aman. Selain itu, presiden tidak lagi bertanggungjawab kepada MPR, karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat.23 Meskipun demikian, MPR tetap dapat memberntikan Presiden dalam masa jabatannya atas usul DPR jika memperhatikan Pasal 7A perubahan ketiga UUD 1945. Namun, hal ini akan sangat bergantung kepada keputusan Mahkamah Konstitusi RI, karena menurut Pasal 7B ayat (1) menyatakan usul pemberhentian 23 vide Pasal 6A, 7A dan 7B serta Pasal 24C ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012 351 Dilematika Putusan Mahkamah Konstitusi Vs Kekuatan Politik dalam Impeachment Presiden Presiden dan/ atau wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum.24 Jadi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut semata-mata atas dasar pertimbangan hukum. Jika dianulir terhadap Pasal 8 ayat (3) UUD 1945, MPR dapat memilih Presiden dan Wakil presiden pengganti apabila terdapat kekosongan jabatan Presiden dan wakil presiden di tengah masa jabatannya secara bersamaan, akan tetapi hasil Presiden terpilih dalam pemilihan Presiden yang dilakukan oleh MPR tersebut hanya karena adanya kekosongan jabatan dalam masa jabatan Presiden. Oleh karena itu, pertanggungjawaban presiden dan wakil presiden yang dipilih oleh MPR tersebut tidak bertanggung jawab kepada MPR sebagai pemilh, melainkan ia tetap bertanggung jawab kepada rakyat, karena pemilihan Presiden oleh MPR itu, bukan dalam rangka masa akhir jabatan sebagaimana lima tahun sekali, tetapi merupakan perpanjangan tangan (sisa jabatan) dari hasil pemilihan Presiden yang dilakukan oleh rakyat secara langsung dalam Pilpres. Jadi tetap konsep kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.25 Jika dicermati ketentuan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 tersebut bersifat dilematis karena masih memberikan kewenangan kepada MPR membolehkan untuk memilih Presiden dan wakil Presiden yang masih ada dalam sisa jabatan Presiden/wakil Presiden hasil pemilihan langsung oleh rakyat. Seyogiayanya pemilihan Presiden dan/atau wakil presiden pengganti (dalam sisa jabatan) diserahkan kembali kepada rakyat ayat (2) dan Pasal 6A UUD RI Tahun 1945, kecuali jika pertimbangannya karena teknis dan karena biaya besar untuk dipilih kembali oleh rakyat, maka kewenangan MPR dalam memilih Presiden pengganti dapat dibenarkan secara teknis, bukan secara yuridis konstitusional. Mahfud MD mengemukakan, bahwa ketentuan konstitusi yang tampaknya mempersulit cara impeachment/penjatuhan Presiden sebenarnya agak ilutif, sebab jika bola politik mengelinding ke arah impeachment, tidak terlalu sulit bagi parpol-parpol untuk melakukan penggalangan politik. Karena itu, Presiden Indonesia siapapun dia tidak boleh meremehkan parpol meski parpol kecil sekalipun dengan hitungan yang sederhana.26 24 25 26 vide Pasal 7A UUD RI Tahun 1945 mengenai bentuk pelanggaran hukumnya Pasal 1 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945. Moh. Mahfud, MD, 2009, Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu, Jakarta: RajaGrafindo Persada, h. 354 352 Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012 Dilematika Putusan Mahkamah Konstitusi Vs Kekuatan Politik dalam Impeachment Presiden Dalam keadaan mekanisme yang demikian, menurut Mahfud terjadilah saling sandera antara Presiden dan partai politik. Parpol menyandera Presiden agar mau menerima sodoran kader untuk kabinet atau minta imbalan politik lainnya. Presiden juga berkepentingan menyandera sebagian Parpol agar tidak menjatuhkannya dengan memberi imbalan politik sekurang-kurangnya Presiden agar terus berusaha agar kalangan Parpol yang melawan tidak mencapai dua pertiga perdua pertiga di DPR dan dua pertiga pertiga perempat di MPR.27 Jadi, meskipun menurut Pasal 7A dan 7B UUD RI 1945 untuk menjatuhkan Presiden tampak sulit, akan tetapi jika bola politik menggelinding untuk menjatuhkan Presiden/Wakil Presiden, maka tidak terlalu sulit untuk dilakukan karena dapat mencari-cari bukti bahwa Presiden/wakil Presiden melanggar salah satu 5 (lima) pelangaran tersebut, dan banyak yang dapat ditemukan tinggal kourum dan kesepakatan partai-partai politik di DPR. Selain itu, dengan sistem politik yang multi partai seperti sekarang, kedudukan Presiden/Wakil Presiden tidak dapat sekuat seperti yang kita bayangkan dalam sistem dwi partai.28 KESIMPULAN Sebagaimana penuis sebutkan di awal, Pasal 7A dan 7B UUD RI Tahun 1945, telah mengatur secara tegas masalah pemberhentian (impeachment) Presiden dan/atau wakil Presiden dalam masa jabatannya, di mana pemberhentian (impeachment) Presiden dan/atau wakil Presiden menurut Pasal tersebut terjadi di dalam 3 (tiga) lembaga, yaitu: Pertama, di DPR sebagai lembaga politik yang mengusulkan kepada Mahkamah Konstitusi mengenai adanya pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden dan/atau wakil Presiden. Kedua, di Mahkamah Konstitusi RI sebagai lembaga pemeriksa dan pemutus/penentu terbukti atau tidaknya Presiden dan/atau wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum. Ketiga, di Majelis Pemusyawaratan Rakyat sebagai pemutus untuk memberhentikan atau tidak memberhentikan Presiden dan/atau wakil Presiden dalam masa jabatannya yang didakwa melakukan pelanggaran hukum. Jika diperhatikan impeachment Presiden ditiga lembaga di atas sepertinya sangat mudah untuk menuju proses impeachment, akan tetapi juga terlihat sangat sulit untuk memakzulkan Presiden dan/atau wakil Presiden jika meihat mekanisme dari Pasal 7A dan 7B UUD RI Tahun 1945. Namun demikian, terjadi atau tidaknya impeachment Presiden dalam masa jabatannya akan 27 28 Ibid., h. 355 Ibid., h. 356 Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012 353 Dilematika Putusan Mahkamah Konstitusi Vs Kekuatan Politik dalam Impeachment Presiden ditentukan oleh kekuatan politik yang mendukungnya meskipun ada keterlibatan Mahkamah Konstitusi RI di dalamnya karena keterlibatan Mahkamah Konstitusi RI hanya sebatas kewajiban bukan kewenangan, sehingga bagi Mahkamah Konstitusi RI putusannya menjadi dilematis karena akan ditentukan oleh kekuatan politik di sidang MPR, selain itu 3 (tiga) dari 9 (sembilan) anggota hakim Mahkamah Konstitusi diajukan oleh Presiden hal itu juga menjadi sangat dilematis. SARAN Atas dasar uraian di atas, maka dapat diajukan saran/rekomendasi sebagai berikut: Perubahan terhadap Pasal 7A dan 7B UUD 1945 tetap diperlukan mengingat pengaturan impeachment dalam Pasal tersebut masih menyisakan masalah. Oleh karena itu disarankan bahwa: (1) kewajiban MK RI memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sebaiknnya dialihkan menjadi kewenangan MK RI sehingga putusan MK RI tidak dilematis menjadi final dan binding serta tidak dapat diuji oleh lembaga lain. (2) Pengajuan Hakim Mahkamah Konstitusi sebaiknya tidak perlu diajukan oleh Presiden, tidak perlu diajukan oleh Mahkamah Agung, juga tidak perlu diajukan oleh DPR, melainkan ditentukan melalui mekanisme rekrutmen seleksi alamiah oleh Komisi Independen sehingga putusan Mahkamah Konstitusi dalam impeachment Presiden benar-benar independent, netral dan berwibawa. Dalam keadaan ini Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan didudukkan sebagai pihak yang menetapkan hakim konstitusi hasil rekrutment seleksi alamiah dari Komisi Independen. 354 Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012 Dilematika Putusan Mahkamah Konstitusi Vs Kekuatan Politik dalam Impeachment Presiden DAFTAR PUSTAKA Asshiddiqie, Jimly, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007. Baroto, Cahyo. “Belajar dari Impeachment Beberapa Negara Lain”, dalam http:// news.okezone.com/read/2010/03/08/58/310152, 8 Maret 2010. Bonny & Novan. “Penolakan pertanggungjawaban Presiden Sebagai Mandataris MPR”, Majalah Hukum dan kemasyarakatan. Jakarta, 1991. dalam Mirza Nasution, “Beberapa Masalah Tentang Pemberhentian Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Kuasi Presidensial Di Indonesia”, Fakultas Hukum Bagian Ilmu Tatanegara Universitas Sumatera Utara Tanpa Tahun. Latif, Abdul. Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokratis. Yogyakarta: CV. Kreasi Total Media, 2007. Mahfud MD, Moh. Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Gama Media, 1999. ------------. Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi. Yogyakarta: Liberty, 1999. ------------. Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009. Nadir, “Memformat Equity and Equality Antara DPR dan DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Publika Jurnal Ilmiah Administrasi Negara FIA Unira Pamekasan Tahun I No. I Januari, 2010. Pound, Roscoe. Pengantar Filsafat Hukum, Terjemahan Mohammad Radjab. Jakarta: Bhratara, 1972. Rahardjo, Satjipto. Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antar Disiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional. Bandung: Sinar Baru, 1985. ------------. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996. Soekanto, Soerjono. Pengantar Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali Press, 1973. Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012 355 Dilematika Putusan Mahkamah Konstitusi Vs Kekuatan Politik dalam Impeachment Presiden Soimin. Impeachment Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Yogyakarta: UII Press, 2009. Schroeder, Richard C. Garis Besar Pemeritahan Amerika. AS: Dinas Penerangan AS, tanpa tahun. Wardani, Kunthi Dyah. Impeachment Dalam Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta: UII Press, 2007. Zoelva, Hamdan. Impeachment Presiden: Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945. Jakarta: Konstitusi Press, 2005. Jimly Asshiddiqie, “Impeachment” dalam legalitas.org.html, diakses Juli 2009. 356 Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012