Karya Sastra Drama: Sastra Lakon - Staff Site Universitas Negeri
advertisement
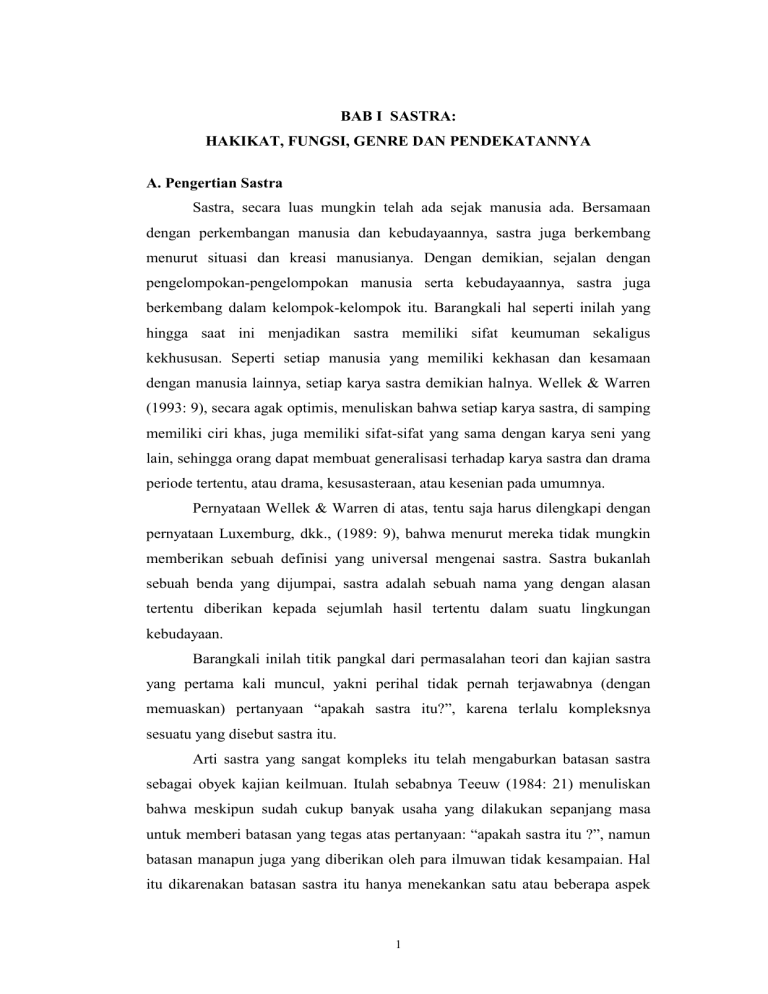
BAB I SASTRA: HAKIKAT, FUNGSI, GENRE DAN PENDEKATANNYA A. Pengertian Sastra Sastra, secara luas mungkin telah ada sejak manusia ada. Bersamaan dengan perkembangan manusia dan kebudayaannya, sastra juga berkembang menurut situasi dan kreasi manusianya. Dengan demikian, sejalan dengan pengelompokan-pengelompokan manusia serta kebudayaannya, sastra juga berkembang dalam kelompok-kelompok itu. Barangkali hal seperti inilah yang hingga saat ini menjadikan sastra memiliki sifat keumuman sekaligus kekhususan. Seperti setiap manusia yang memiliki kekhasan dan kesamaan dengan manusia lainnya, setiap karya sastra demikian halnya. Wellek & Warren (1993: 9), secara agak optimis, menuliskan bahwa setiap karya sastra, di samping memiliki ciri khas, juga memiliki sifat-sifat yang sama dengan karya seni yang lain, sehingga orang dapat membuat generalisasi terhadap karya sastra dan drama periode tertentu, atau drama, kesusasteraan, atau kesenian pada umumnya. Pernyataan Wellek & Warren di atas, tentu saja harus dilengkapi dengan pernyataan Luxemburg, dkk., (1989: 9), bahwa menurut mereka tidak mungkin memberikan sebuah definisi yang universal mengenai sastra. Sastra bukanlah sebuah benda yang dijumpai, sastra adalah sebuah nama yang dengan alasan tertentu diberikan kepada sejumlah hasil tertentu dalam suatu lingkungan kebudayaan. Barangkali inilah titik pangkal dari permasalahan teori dan kajian sastra yang pertama kali muncul, yakni perihal tidak pernah terjawabnya (dengan memuaskan) pertanyaan “apakah sastra itu?”, karena terlalu kompleksnya sesuatu yang disebut sastra itu. Arti sastra yang sangat kompleks itu telah mengaburkan batasan sastra sebagai obyek kajian keilmuan. Itulah sebabnya Teeuw (1984: 21) menuliskan bahwa meskipun sudah cukup banyak usaha yang dilakukan sepanjang masa untuk memberi batasan yang tegas atas pertanyaan: “apakah sastra itu ?”, namun batasan manapun juga yang diberikan oleh para ilmuwan tidak kesampaian. Hal itu dikarenakan batasan sastra itu hanya menekankan satu atau beberapa aspek 1 saja, atau hanya berlaku untuk sastra tertentu saja, atau sebaliknya, terlalu luas dan longgar sehingga melingkupi banyak hal yang jelas bukan sastra lagi. Menurut Luxemburg dkk (1989: 4) kegagalan definisi itu antara lain sebagai berikut. 1. Karena orang ingin mendefinisikan terlalu banyak sekaligus, sering menggunakan dua kriteria sekaligus, sering menggunakan definisi deskriptif dan definisi evaluatif sekaligus, dengan menuilai baik dan tidaknya suatu karya sastra. 2. Karena menggunakan definisi “ontologis” mengenai sastra, yakni mengungkap hakikat sebuah karya sastra. Padahal mengingat kompleksnya obyek sastra, mestinya sastra didefinisikan di dalam situasi pemakai atau pembaca sastra. Norma dan deskripsi sering dicampuradukkan, padahal suatu karya bagi satu orang bisa termasuk sastra, bagi orang lain mungkin tidak. 3. Anggapan mengenai sastra sering ditentukan oleh sastra Barat, khususnya sejak jaman renaisance, tanpa memperhitungkan bentukbentuk sastra di luar Eropa. Sastra India, Melayu, Jawa dan sebagainya tentu memiliki kekhasannya masing-masing, apalagi kalau dipisahkan dari jaman-jaman tertentu. 4. Definisi oleh ahli yang sering memuaskan untuk diterapkan pada sejumlah jenis sastra, tidak cocok untuk diterapkan pada sastra secara umum. Pada berbagai hal secara umum, untuk mendefinisikan sesuatu itu dapat didekati dari namanya. Secara etimologis, kata sastra dalam bahasa Indonesia (dalam bahasa Inggris sering disebut literature dan dalam bahasa Perancis disebut litterature) berasal dari bahasa Sanskerta: akar kata ‘sas-, dalam kata kerja turunan berarti “mengarahkan, mengajar, memberi petunjuk atau instruksi”. Akhiran -tra, biasanya menunjukkan “alat, sarana”. Jadi sastra dapat berarti “alat untuk mengajar, buku petunjuk, buku instruksi atau pengajaran”. Kata lain yang sering dipergunakan ialah kata susastra yang berasal dari kata sastra mendapat awalan su- yang berarti “baik, indah”. Jadi kata susastra dapat berarti “sastra yang baik” atau “sastra yang indah” yang dalam bahasa 2 Perancis atau Inggris dipergunakan istilah belles-lettres. Menurut Gonda kata susastra tidak dipergunakan dalam bahasa Jawa Kuna, sehingga istilah susastra adalah ciptaan Jawa atau Melayu yang muncul kemudian (Teeuw, 1984: 23). Batasan secara etimologis tersebut, juga belum maksimal. Tidak semua alat untuk mengajar bisa dikategorikan sebagai sastra, walaupun dalam arti sebaliknya, semua sastra “dapat” dipergunakan sebagai alat untuk mengajar. Luxemburg, dkk. (1989: 9-11) menyebutkan sejumlah faktor yang dewasa ini mendorong para pembaca untuk menyebut teks ini sastra dan teks itu bukan sastra, yakni sebagai berikut. (1) Yang dikaitkan dengan pengertian sastra ialah teks-teks yang tidak melulu untuk tujuan komunikatif praktis yang bersifat sementara waktu saja. (2) Bagi sastra Barat dewasa ini kebanyakan teks drama dan cerita mengandung fiksionalitas. Bagi orang Yunani dahulu, fiksionalitas tidak relevan untuk membatasi pengertian sastra, dan di Cina dahulu teks-teks rekaan justru tidak dianggap sastra. (3) Dalam hal puisi lirik, dipergunakan konvensi distansi untuk mengambil jarak sehingga tidak setiap puisi lirik dinamakan rekaan. (4) Bahan sastra diolah secara istimewa dan dengan cara yang berbedabeda sehingga misalnya, pengertian bahasa puitik tidak pernah bisa dibatasi secara mutlak. (5) Sebuah karya sastra dapat dibaca menurut tahap-tahap arti yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan itu tergantung pada mutu sastra yang bersangkutan dan kemampuan pembaca dalam menggauli teksteks sastra. (6) Karya-karya bukan fiksi dan juga bukan puisi, karena ada kemiripan tertentu digolongkan dalam sastra, yakni karya-karya naratif, seperti biografi-biografi dan karya-karya yang menonjol karena bentuk dan gayanya. Surat-menyurat antar sastrawan lebih mudah dikategorikan sebagai sastra daripada antar sejarawan. 3 (7) Terdapat karya-karya yang semula tidak masuk sastra, kemudian dikategorikan sastra. Misalnya kitab-kitab babad bukan sekedar penulisan sejarah tetapi sastra. Wellek & Warren (1993: 11-16) mencatat bahwa untuk mendefinisikan sastra ada beberapa cara, yakni sebagai berikut. (1) Salah satu batasan sastra adalah segala sesuatu yang tertulis atau tercetak. Pengertian ini seperti pengertian etimologis pada kata literature (Inggris). Jadi ilmuwan sastra dapat mempelajari profesi kedokteran, ekonomi, dsb. Dengan demikian seperti yang dikemukakan Edwin Greenlaw (teoritikus sastra Inggris) bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan sejarah kebudayaan termasuk dalam wilayah sastra. Demikian pula menurut banyak praktisi ilmu lain, sastra bukan hanya berkaitan erat dengan sejarah kebudayaan tetapi memang identik. Dalam hal ini Wellek & Warren mengomentari bahwa akhirnya studi semacam ini bukan studi sastra lagi. Studi yang berkaitan dengan sejarah kebudayaan cenderung menggeser studi sastra yang murni, karena dalam studi kebudayaan semua perbedaan dalam teks sastra diabaikan. Bagi sastra Jawa, seperti halnya pada banyak budaya lain, batasan seperti ini tidak menguntungkan karena Jawa memiliki tradisi sastra lisan yang sangat kuat. (2) Cara lain untuk membatasi definisi pada sastra adalah membatasi pada “mahakarya” (great books), yaitu buku-buku yang dianggap “menonjol karena bentuk dan ekspresi sastranya”. Dalam hal ini kriteria penilaiannya adalah segi estetis atau nilai estetis dikombinasikan dengan nilai ilmiah. Di antara puisi lirik, drama dan cerita rekaan, mahakarya dipilih berdasarkan pertimbangan estetis. Sedang buku-buku lain dipilih karena reputasinya atau kecemerlangan ilmiahnya, ditambah penilaian estetis dalam gaya bahasa, komposisi, dan kekuatan penyampaiannya. Dalam hal ini sastra atau bukan sastra ditentukan oleh penilaian. Di samping itu sejarah, filsafat dan ilmu pengetahuan termasuk dalam sastra. Dalam sastra Jawa kuna, dan 4 sebagian sastra Jawa modern, memang banyak karya sastra yang berisi ilmu pengetahuan atau sejarah, namun sering dikategorikan sebagai karya sastra karena gaya bahasanya, antara lain Negarakertagama (Jawa kuna) dan karya sastra Babad (Jawa modern) yang sebagian besar berisi sejarah. (3) Menurut Wellek & Warren, pengertian sastra yang paling tepat diterapkan pada seni sastra, yakni sastra sebagai karya imajinatif. Istilah lainnya adalah fiksi (fiction) dan puisi (poetry), namun pengertiannya lebih sempit. Sedang penggunaan istilah sastra imajinatif (imaginative literature) dan belles latters (tulisan yang indah dan sopan) kurang lebih menyerupai pengertian etimologis kata susastra, dinilai kurang cocok dan bisa memberi pengertian yang keliru. Istilah Inggris, literature, juga lebih sempit pengertiannya. Istilah yang agak luas pengertiannya dan lebih cocok adalah istilah dari Jerman wortkuns dan dari Rusia slovesnost. (4) Cara lain yang dilakukan untuk memecahkan definisi sastra adalah melalui kategorisasi bahasa. Bahasa adalah media yang dipergunakan oleh sastra. Namun demikian sastra tidak memiliki media secara khusus, karena bahasa juga dipergunakan sebagai media komunikasi oleh bidang keilmuan lain. Oleh karena itu membatasi sastra dari segi bahasanya juga tidak sesederhana itu. Wellek & Warren (1993: 16) juga menyatakan bahwa untuk melihat penggunaan bahasa yang khas sastra, harus dibedakan antara bahasa sastra, bahasa ilmiah dan bahasa sehari-hari. Hal ini pernah dilakukan oleh Thomas Clark Pollock dalam bukunya The Nature of Literature. Namun demikian buku itu tidak memuaskan terutama dalam membedakan bahasa sastra dengan bahasa sehari-hari. Antara bahasa ilmiah dengan bahasa sastra memang agak mudah dibedakan. Bahasa ilmiah bersifat denotatif , yakni ada kecocokan antara tanda (sign) dengan yang diacu (referent). Jadi bahasa ilmiah cenderung menyerupai sistem tanda matematika atau logika simbolis. 5 Bahasa sastra, dibanding bahasa ilmiah, penuh ambiguitas dan homonim (kata-kata yang sama bunyinya tetapi berbeda artinya), serta memiliki kategorikategori yang tak beraturan dan tak rasional. Bahasa sastra juga penuh dengan asosiasi, mengacu pada ungkapan atau karya yang diciptakan sebelumnya. Dengan kata lain bahasa sastra sangat konotatif sifatnya. Bahasa sastra memiliki fungsi ekspresif, menunjukkan nada (tone) dan sikap pembicara atau penulisnya. Bahasa sastra berusaha mempengaruhi, membujuk dan pada akhirnya mengubah sikap pembaca. Disamping itu yang dipentingkan dalam bahasa sastra adalah tanda, simbolisme suara dari kata-kata. Berbagai teknik diciptakan untuk menarik perhatian pembaca. Membedakan antara bahasa sastra dengan bahasa sehari-hari lebih sulit. Bahasa sehari-hari sering juga bersifat ekspresif. Yang jelas, perbedaan pragmatisnya ialah bahwa segala sesuatu yang mendorong orang untuk melakukan tindakan langsung yang kongkrit sukar untuk diterima sebagai puisi (baca: sastra). Dalam hubungannya dengan bahasa, khususnya bahasa tulis, Teeuw (1984 30-38) memberikan beberapa catatan sebagai berikut. (1) Dalam sastra tulis terdapat keindahan bahasa, yakni pemakaian bahasa yang tepat dan sempurna. Disamping itu dalam sastra tulis sering memberi banyak kemungkinan untuk menciptakan keambiguan, makna ganda, yang sering dianggap sebagai ciri khas bahasa sastra. (2) Dalam sastra tulis, ambiguitas diri penulis yang tidak langsung dihadapi oleh pembaca, sering dimanfaatkan bahkan dieksploitasi secara sangat halus. Tokoh aku dalam karya sastra belum tentu identik dengan penulisnya. (3) Karena hubungan antara karya sastra dengan penulisnya terputus, dengan sendirinya tulisan itu menjadi sangat penting dan mandiri. Jadi karya sastra bukanlah tindak komunikasi biasa dan memunculkan bermacam-macam konvensi yang harus dikuasai pembaca dalam memahami sastra (4) Sastra adalah dunia dalam kata dan dalam pemahamannya tidak dibantu lagi oleh penulisnya sehingga tergantung pada kata. 6 (5) Tulisan dapat diulang baca, sedang konvensi sastranya dapat berubahubah sehingga interpretasi sastra dapat ditinjau lagi disesuaikan dengan informasi baru. (6) Reproduksi sastra sangat mungkin terjadi sehingga dimungkinkan terjadinya perubahan atau pemantapan sehingga terjadi variasi makna. Bagi peneliti hal itu justru memperluas lahan kajian. Bagi pembaca memungkinkan terpenuhi seleranya. (7) Reproduksi sastra dalam berbagai jaman, berbagai bahasa dan budaya menjadikan sastra menjadi gejala sejarah dengan segala akibatnya. Saat ini orang bisa membaca karya Homeros 30 abad yang lalu, atau karya Prapanca pada abad XIV. Kesinambungan kebudayaan sebagian besar tergantung dari penemuan tulisan dan abjad. Namun demikian penafsiran sastra kadang menjadi berbeda dari masa ke masa. Perbedaan penafsiran itu menjadi permasalahan apakah hal ini justru sebagai kekayaan sastra atau sebaliknya, harus berusaha menginterpretasi sesuai dengan maksud awal (asli)-nya. Teeuw menegaskan bahwa sastra bukan hanya dalam rangka sastra tulis, karena ada sastra yang hidup dan berkembang dalam bentuk sastra lisan. Tujuh catatan dalan hubungannya dengan sastra tulis di atas tidak serta merta dapat diterapkan pada sastra lisan, namun setidak-tidaknya terdapat kemiripan terutama pada nomor 1, 2, dan 5. Dalam sastra sering sekali ada bentuk campuran antara sastra tulis dengan sastra lisan, misalnya banyak tersebar di Indonesia. Pada akhirnya Teeuw berkesimpulan bahwa tidak ada kriteria yang jelas yang dapat diambil dari perbedaan pemakaian bahasa lisan dan bahasa tulis untuk membatasi sastra sebagai gejala yang khas. Ada pemakaian bahasa lisan dan tulis yang sastra, ada pula yang bukan sastra; sebaliknya ada sastra tulis dan ada sastra lisan. Tolok ukur untuk membedakan sastra dan bukan sastra harus dicari di bidang lain. Dengan demikian semakin komplekslah permasalahan yang dihadapi untuk memberikan batasan antara sastra dan bukan sastra. Namun demikian ada sejumlah pengertian yang berlaku pada zaman Romantik yang menurut Luxemburg dkk. (1989: 5 ) hingga saat ini masih selalu dipakai, sebagai berikut. 7 (1) Sastra merupakan sebuah ciptaan, sebuah kreasi, bukan semata-mata sebuah imitasi. Sastra terutama merupakan luapan emosi yang spontan. Unsur kreativitas dan spontanitas dewasa ini pun masih sering dijadikan sebagai pedoman (2) Sastra bersifat otonom, tidak mengacu pada sesuatu yang lain; sastra tidak bersifat komunikatif. Sang penyair hanya mencari keseralarasan di dalam karyanya sendiri. Misalnya kaum formalis dari Rusia di awal abad XX (masih) menganggap bahwa cara pengungkapan merupakan ciri khas bagi kesastraan. Kesastraan ditentukan oleh cara bahannya disajikan. Bahan puisi ialah bahasa serta subyeknya, sedang bahan naratif adalah sejarah atau peristiwa yang diceritakan. (3) Karya sastra yang otonom itu bercirikan suatu koherensi. Pengertian koherensi itu dapat ditafsirkan sebagai suatu keselarasan yang mendalam antara bentuk dan isi. Setiap isi berkaitan dengan bentuk atau ungkapan tertentu. Seperti bentuk dan isi saling berhubungan, demikian bagian dan keseluruhan kait-mengait secara erat sehingga saling menerangkan. (4) Sastra menghidangkan sebuah sintesa antara hal-hal yang saling bertentangan, antara yang disadari dengan yang tidak, antara pria dan wanita, antara roh dan benda, dsb. Misalnya aliran New critics di Amerika (masih) menganggap bahwa bahasa puisi adalah bahasa paradoks. (5) Sastra mengungkapkan yang tak terungkapkan. Oleh sastra ditimbulkan asosiasi dan konotasi. Dalam teks sastra ada sederet arti yang tidak diungkapkan dalam bahasa sehari-hari. Misalnya Roland Barthes (masih) menyatakan bahwa menafsirkan sebuah teks sastra tidak boleh menunjukkan satu arti saja, melainkan membeberkan aneka kemungkinan. Sebagai bahan pembanding dan langkah awal untuk melakukan pengkajian pada khasanah kesasteraan, kiranya perlu juga disampaikan beberapa batasan sastra yang pernah dituliskan oleh beberapa pengamat sastra di Indonesia. 8 Andre Hardjana dalam bukunya Kritik Sastra: Sebuah Pengantar (1983: 10), menggunakan batasan sastra yang diberikan oleh William Henry Hudson, yakni bahwa sastra sebagai “pengungkapan baku dari apa yang telah disaksikan orang dalam kehidupan, apa yang telah dialami orang tentang kehidupan, apa yang telah dipermenungkan, dan dirasakan orang mengenai segi-segi kehidupan yang paling menarik minat secara langsung lagi kuat - pada hakikatnya adalah suatu pengungkapan kehidupan lewat bentuk bahasa. Atar Semi, dalam bukunya Anatomi Sastra (1988: 2) menyatakan bahwa sastra adalah suatu bentuk dan hasil pekerjaan seni kreatif yang obyeknya adalah manusia dan kehidupannya, dengan menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Panuti Sudjiman, dalam edisinya Kamus Istilah Sastra (1986: 68), menuliskan sastra adalah karya lisan atau tertulis yang memiliki berbagai ciri keunggulan seperti keorisinalan, keartistikan, keindahan dalam isi dan ungkapannya. Jakob Sumarjo, dalam bukunya Memahami Kesusastraan (1984), menyatakan bahwa kesusasteraan dapat dilihat sebagai memiliki badan dan jiwa. Jiwa sastra berupa pikiran, perasaan dan pengalaman manusia, sedang badannya adalah ungkapan bahasa yang indah, sehingga memberikan hiburan bagi pembacanya. B. Fungsi Sastra Antara sastra, fungsi dan sifatnya adalah sesuatu yang koheren. Membicarakan apa itu sastra berarti juga menyinggung bagaimanakah sastra itu dan untuk apa. Fungsi suatu benda sesuai dengan sifat-sifat benda itu. Fungsi puisi sesuai dengan sifat-sifat puisi itu. Setelah dicermati beberapa pengertian sastra di atas, maka terdapat unsur-unsur yang terdapat dalam sastra, misalnya kreatif, keindahan, menghibur, baik, bermanfaat, contoh-contoh tentang manusia dan kehidupannya, dsb. Unsur-unsur tersebut merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melacak, menangkap atau merumuskan fungsinya. Fungsi sastra sering berubah-ubah menurut pandangan masyarakat terhadap sastra itu sendiri. Pada akhir abad ke-19, dengan munculnya doktrin “seni untuk seni”, tentu saja fungsi sastra juga mengalami perubahan, yakni 9 dalam rangka mengabdi pada seni. Demikian juga pada abad ke-20 dengan adanya doktrin “poesie pure” atau puisi murni. Pada masa renaisance di Amerika, Edgar Allan Poe mengkritik konsep bahwa puisi bersifat didaktis, yang dalam istilah Poe disebut didactic heresy yakni sastra berfungsi menghibur dan sekaligus mengajarkan sesuatu. Namun demikian, menurut Wellek & Warren (1993: 24), bila ditinjau dari sejarah estetika, konsep dan fungsi sastra pada dasarnya tidak berubah, sejauh konsep-konsep itu dituangkan dalam istilah-istilah konseptual yang umum. Di bawah ini beberapa catatan Wellek & Warren dalam hal fungsi sastra. 1. Fungsi Dulce dan Utile Horace (Horatius) pernah mengemukakan pendapatnya bahwa sastra (puisi) harus memenuhi fungsi dulce dan utile: puisi itu indah dan berguna. Konsep indah dan berguna itu, harus berlaku sekaligus, karena bila indah saja berarti puisi itu menghibur saja dan cenderung bermain-main sehingga mengesampingkan ketekunan, keahlian, dan perencanaan sungguh-sungguh dari penyairnya. Sebaliknya, bila berguna saja, berarti melupakan kesenangan yang ditimbulkan oleh puisi. Dalam arti luas, konsep berguna tidak hanya dalam rangka berisi ajaranajaran moral, tetapi berarti “tidak membuang-buang waktu”, dan indah berarti “tidak membosankan”, “bukan kewajiban” atau ”memberikan kesenangan”, maka fungsi itu telah terbukti, misalnya, Hegel mendapatkan fungsi itu dalam drama kesenangannya Antigone. Konsep indah dan berguna tersebut harus saling mengisi. Dalam sastra, kesenangan tidak hanya dalam arti fisik, tetapi lebih dari itu, yakni kontemplasi yang tidak mencari keuntungan. Sedang manfaatnya keseriusan yang bersifat didaktis, adalah keseriusan yang menyenangkan, keseriusan estetis, keseriusan persepsi. 2. Fungsi Khusus Sastra Apakah sastra memiliki manfaat yang berbeda dengan sejarah, filsafat, musik atau bidang-bidang lainnya? Aristoteles pernah mengemukakan diktumnya 10 yang terkenal, bahwa puisi lebih filosofis dari sejarah, karena sejarah berkaitan dengan hal-hal yang telah terjadi, sedang puisi berkaitan dengan hal-hal yang bisa terjadi, yakni hal-hal yang umum dan yang mungkin. Pada jaman neoklasik, Samuel Johnson masih menganggap puisi menyampaikan hal-hal yang umum (grandeur of generality), sedang para teoritikus abad ke-20 telah menekankan sifat khusus puisi. Teori sastra dan apologetics (pembelaan terhadap sastra) juga menekankan sifat tipikal sastra. Sastra dapat dianggap lebih umum dari sejarah dan biografi, tetapi lebih khusus dari psikologi dan sosiologi. Namun tingkat keumuman dan kekususannya berbeda-beda tiap sastra dan tiap periode. 3. Sastra dan Psikologi Salah satu nilai (fungsi) kognitif drama dan novel adalah segi psikologisnya. Menurut Wellek & Warren pernyataan yang sering terdengar adalah bahwa novelis dapat mengajarkan lebih banyak tentang sifat-sifat manusia daripada psikolog. Karen Horney menunjuk pada Dostoyevsky, Shakespeare, Ibsen, dan Balzac sebagai sumber studi psikologi. E.M. Forster menyatakan bahwa novel sangat berjasa mengungkapkan kehidupan batin tokoh-tokohnya. 4. Sastra dan Kebenaran Dalam hubungannya dengan kebenaran, Max Eastman menyangkal bahwa pada abad ilmu pengetahuan, “pikiran sastra” dapat mengungkapkan kebenaran. Bagi Eastman, “pikiran sastra” adalah pikiran amatir tanpa keahlian tertentu (khusus) dan warisan jaman pra-ilmu pengetahuan yang memanfaatkan sarana verbal untuk menciptakan “kebenaran”. Menurut pendapatnya, kebenaran dalam karya sastra sama dengan kebenaran di luar karya sastra, yakni pengetahuan sistematik yang dapat dibuktikan. Menurut Eastman, tugas penyair bukan menemukan dan menyampaikan pengetahuan. Fungsi utamanya adalah membuat orang melihat apa yang sehari-hari sudah ada di depannya, dan membayangkan apa yang secara konseptual dan nyata sebenarnya sudah diketahuinya. Menurut Wellek & Warren kontroversi antara ada dan tidaknya kebenaran dalam sastra bersifat semantik antara “pengetahuan”, “kebenaran”, 11 “kognisi”, dan “kebijaksanaan”. Kalau kebenaran diartikan sebagai konsep dan proposisi, maka seni, termasuk seni sastra, bukan bentuk kebenaran. Apalagi jika batasan positif reduktif diterapkan, yakni bahwa kebenaran dibatasi pada apa yang dapat dibuktikan secara metodis oleh siapa saja. Namun secara umum, ahliahli estetika tidak menolak bahwa “kebenaran” merupakan kriteria atau ciri khas seni. Hal ini dikarenakan: 1) kebenaran adalah kehormatan sehingga memberi penghormatan pada seni; 2) bila seni itu tidak “benar” berarti seni itu “bohong” seperti tuduhan Plato. Menurut Wellek & Warren sastra rekaan adalah fiksi sebuah “tiruan kehidupan” yang artistik dan verbal. Lawan kata fiksi bukanlah “kebenaran” melainkan “fakta” atau “keberadaan waktu dan ruang”. Dalam sastra hal-hal yang mungkin terjadi lebih berterima daripada “fakta”. Ada dua tipe dasar pengetahuan yang menggunakan sistem bahasa yang terdiri atas tanda-tanda: 1) ilmu pengetahuan yang memakai cara diskursif, yakni membuat uraian panjang 2) seni yang memakai cara presentasional, yakni langsung memberi wujud atau contoh. Sistem pertama dipakai oleh para pemikir dan filsuf. Yang kedua meliputi mitos keagamaan dan puisi (sastra). Susanne K. Langer melihat sastra dalam beberapa hal, merupakan campuran arti bentuk diskursif dan presentasional. Dalam hal ini Archibald MacLeish dalam bukunya Ars Poetica menjabarkan sifat indah sastra dan filsafat, bahwa puisi sama seriusnya dan sama pentingnya dengan filsafat (ilmu pengetahuan, kebijaksanaan) dan memiliki persamaan dengan kebenaran; jadi mirip kebenaran. 5. Sastra dan Propaganda Dalam hubungannya dengan pandangan bahwa seni adalah propaganda, perlu dijelaskan batasan propaganda itu. Dalam bahasa populer, propaganda dikaitkan dengan doktrin yang berbahaya, yang disebarkan oleh orang yang tidak dapat dipercaya. Dalam propaganda tersirat unsur-unsur perhitungan, maksud tertentu, dan biasanya diterapkan dalam doktrin atau program tertentu pula. Dengan demikian sejumlah seni dapat digolongkan sebagai propaganda. Sedang seni yang baik, seni yang hebat bukanlah propaganda. Bila istilah propaganda diperluas hingga mencakup “segala macam usaha yang dilakukan dengan sadar atau tidak untuk mempengaruhi pembaca agar menerima sikap hidup tertentu”, 12 maka semua seniman melakukan propaganda. Bahkan, seniman yang bertanggung jawab wajib secara moral melakukan propaganda. Menurut Montgomery Belgion seorang sastrawan adalah pelaku propaganda yang tak bertanggung jawab (irresponsible propagandist). Menurut Eliot, kadar tanggung jawab dinilai dari maksud pengarang dan dampak sejarah. Menurut Wellek & Warren pandangan hidup yang diartikulasikan pengarang (yang) bertanggung jawab tidak sesederhana karya propaganda populer. Pandangan hidup yang kompleks dalam karya sastra tidak bisa mendorong orang melakukan tindakan yang naif dan sembrono dengan sugesti hipnotis. 6. Sastra dan Fungsi Katarsis Chatarsis merupakan istilah bahasa Yunani yang dipakai oleh Aristoteles dalam bukunya The Poetics dengan makna yang hingga saat ini masih diperdebatkan. Namun yang jelas masalah yang timbul dari penggunaan istilah itu ialah adanya fungsi sastra yang menurut sejumlah teoritikus, untuk membebaskan pembaca dan penulisnya dari tekanan emosi. Bagi penulis, mengekspresikan emosi berarti melepaskan diri dari emosi itu. Bagi pembaca, emosi mereka sudah diberi fokus dalam karya sastra, dan lepas (terbebas) pada akhir pengalaman estetis mereka sehingga mereka mendapatkan “ketenangan pikiran”. Berbeda dengan hal tersebut, menurut Plato, drama tragedi dan drama komedi justru memupuk dan menyuburkan emosi yang seharusnya di matikan. 7. Fungsi Sastra di Indonesia Dari uraian yang bersifat umum di atas, kiranya perlu juga dicantumkan di sini fungsi sastra menurut pengamat sastra di Indonesia. Menurut Atar Semi (1988) ada tiga tugas dan fungsi sastra, yakni sebagai berikut. Pertama, sebagai alat penting pemikir-pemikir untuk menggerakkan pembaca kepada kenyataan dan menolongnya mengambil suatu keputusan bila ia mendapat masalah. Pengarang bertugas mengikuti dan memikirkan tentang budaya dan nilai-nilai bangsanya pada masa ia hidup untuk kemudian dicurahkan ke dalam karya sastra yang baik. Salah satu ukuran sastra yang baik ialah sastra yang dapat menggambarkan kebudayaan masyarakat pemiliknya pada jamannya. 13 Karya sastra memberikan kearifan alternatif untuk menolong mengatasi masalah kehidupan. Pada jaman globalisasi ini interaksi kebudayaan antar bangsa terjadi secara intensif sehingga budaya yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa pun akan mempengaruhi, menggeser, bahkan menggantikan kebudayaan bangsa yang ada sebelumnya. Di sinilah diharapkan peran sastra dapat menangkal pengaruhpengaruh negatif tersebut. Kedua, sastra berfungsi sebagai alat untuk meneruskan tradisi suatu bangsa, baik kepada masyarakat sejaman maupun generasi mendatang. Dengan kata lain sebagai alat penerus tradisi dari generasi ke generasi berikutnya, baik berupa cara berpikir, kepercayaan, kebiasaan, pengalaman sejarah, rasa keindahan, bahasa, serta bentuk-bentuk kebudayaannya. Ketiga, menjadikan dirinya sebagai suatu tempat dimana nilai kemanusiaan diberi perhatian (dihargai) sewajarnya, dipertahankan dan disebarluaskan, terutama ditengah-tengah kehidupan modern yang ditandai dengan majunya sains dan teknologi dengan pesat. Dengan demikian fungsi sastra, dalam hal ini seperti pembicaraanpembicaraan di atasnya, tidak dapat digeneralisasikan begitu saja dan memerlukan penjelasan-penjelasan yang lebih berterima dengan mempertimbangkan kondisi kontekstualnya. Dalam hal ini, sebagai perenungan lebih lanjut dapat dibaca lebih jauh tentang perdebatan sastra kontekstual (Heryanto, 1985) C. Genre Sastra Pembicaraan tentang genre sastra, seperti halnya pembicaraan tentang fungsi sastra dan teori sastra pada umumnya, telah berlangsung lama. Dalam sejarahnya, batasan mengenai genre sastra juga bersifat sangat dinamis dan berbeda-beda. Jenis sastra terjadi oleh karena konvensi sastra yang berlaku pada suatu karya yang membentuk ciri karya tersebut. Menurut N.H. Pearson jenis sastra dapat dianggap sebagai suatu perintah kelembagaan yang memaksa pengarangnya sendiri. Menurut Harry Levin, jenis sastra adalah suatu “lembaga”, seperti halnya gereja, universitas, atau negara. Jenis sastra itu dinamis seperti 14 halnya sebuah institusi yang boleh diikuti atau tidak, atau boleh dirubah. Sedang menurut A. Thibaudet teori genre adalah suatu prinsip keteraturan: sastra dan sejarah sastra diklasifikasikan tidak berdasarkan waktu atau tempat (periode atau pembagian sastra nasional), tetapi berdasarkan tipe struktur atau susunan sastra tertentu (Wellek & Warren, 1993: 298-300). Asia Padmopuspito (1991: 2) mengutip beberapa definisi genre sastra dari beberapa pakar sastra, antara lain sebagai berikut. Menurut Shipley, genre adalah jenis atau kelas yang di dalamnya termasuk karya sastra. Hasry Shaw menyatakan bahwa genre adalah kategori atau kelas usaha seni yang memiliki bentuk, teknik atau isi khusus. Di antara genre dalam sastra termasuk novel, cerita pendek, esai, epik, dsb. Menurut Abrams, genre merupakan istilah untuk menandai jenis sastra atau bentuk sastra. Nama genre sastra pada periode kuno: tragedi, komedi, epik, satire, novel, esai dan biografi. Pada periode renaisan: epik, tragedi, komedi, sejarah pastoral, komik pastoral, dsb. Menurut Hirsch, cara terbaik untuk mendefinisikan genre ialah dengan melukiskan unsur-unsur di dalam kelompok teks sempit yang mempunyai hubungan sejarah secara langsung. Aristoteles dalam tulisannya yang berjudul Poetika meletakkan dasar untuk studi jenis sastra. Ia sadar bahwa karya sastra dapat digolongkan menurut berbagai kriteria; menurutnya ada tiga macam kriteria yang dapat dijadikan patokan (berdasarkan sastra Yunani klasik, namun teori ini banyak cocoknya untuk sastra lain), sebagai berikut (Teeuw, 1984: 108). 1. Sarana perwujudannya (media of representation): a. prosa b. puisi: yang satu matra (contohnya: syair) dan yang lebih dari satu matra (contohnya tragedi, kakawin) (Dalam pembagian ini pada prisipnya tidak dibedakan antara sastra dan bukan sastra) 2. Obyek perwujudan (objects of representation): yang menjadi obyek pada prinsipnya manusia, tetapi ada tiga kemungkinan: a. manusia rekaan lebih agung dari manusia nyata: tragedi, epik Homeros, cerita Panji 15 b. manusia rekaan lebih hina dari manusia nyata: komedi, lenong c. manusia rekaan sama dengan manusia nyata: Cleophon (bila ketika itu sudah ada roman pastilah masuk kategori ini) 3. Ragam Perwujudannya (manner of poetic representation): a. teks sebagian terdiri dari cerita, sebagian disajikan melalui ujaran tokoh (dialog): epik b. yang berbicara si aku lirik penyair: lirik c. yang berbicara para tokoh saja: drama Teeuw (1984: 110-113) juga mencatat pendapat beberapa pakar yang mempermasalahkan dinamika jenis sastra, sebagai berikut. Menurut Culler, pada asasnya fungsi konvensi jenis sastra ialah mengadakan perjanjian antara penulis dan pembaca, agar terpenuhi harapan tertentu yang relevan, dan dengan demikian dimungkinkan sekaligus penyesuaian dengan dan penyimpangan dari ragam keterpahaman yang telah diterima. Menurut Todorov, batasan jenis sastra oleh karena itu merupakan suatu kian kemari yang terus menerus antara deskripsi fakta-fakta dan abstraksi teori. Menurut Claudio Guillen, jenis sastra adalah undangan atau tantangan untuk melahirkan wujud. Konsep jenis memandang ke depan dan ke belakang sekaligus. Ke belakang ke karya sastra yang sudah ada dan ke depan ke calon penulis. Menurut Todorov, setiap karya agung, per definisi, menciptakan jenis sastranya sendiri. Setiap karya agung menetapkan terwujudnya dua jenis, kenyataan dan norma, norma jenis yang dilampauinya yang menguasai sastra sebelumnya, dan norma jenis yang diciptakannya. Demikian juga menurut Hans Robert Jausz, bahwa jenis sastra per definisi tidak bisa hidup untuk selamanya, karya agung justru melampaui batas konvensi yang berlaku dan membuka kemungkinan baru untuk perkembangan jenis sastra. Jenis sastra bukanlah sistem yang beku, kaku, tetapi berubah terus, luwes dan lincah. Peneliti sastra harus mengikuti perkembangan itu dalam penelitiannya. Teeuw menambahkan bahwa dalam penelitian sistem jenis sastra, tidak ada garis pemisah yang jelas antara pendekatan diakronik dan sinkronik: karya sastra selalu berada dalam ketegangan dengan karya-karya yang diciptakan sebelumnya. Sehubungan dengan pernyataan tersebut Luxemburg dkk. (1989: 107) menuliskan bahwa penjenisan sering kali tidak hanya deskriptif tetapi juga 16 preskriptif, yakni membuat peraturan-peraturan, sehingga pengarang akan bangga bila dapat memenuhinya. Hal inilah yang disebut dengan estetika identitas. Sedang sikap pertentangan yang mendobrak peraturan-peraturan (konvensi) jenis sastra tertentu disebut estetika oposisi. Dalam sejarah sastra di Indonesia juga banyak sastrawan yang terkenal dengan penentangan konvensi dan pembaruan-pembaruannya yang kemudian diikuti oleh sastrawan-sastrawan di belakangnya yang kemudian menyuarakan jenis sastra baru, misalnya Chairil Anwar. Dalam sastra Jawa dikenal nama Intojo yang mengenalkan jenis soneta pada sastra Jawa sehingga ia disebut sebagai bapak soneta sastra Jawa Modern. Juga dikenal nama Iesmaniasita yang memberontak aturan-aturan tradisi sastra Jawa sebelumnya. Ia menuliskan pemberontakannya dalam puisinya yang berjudul Kowe Wis Lega? dan cerpen Jawanya Tiyupan Pedhut Anjasmara. Puisi Kowe Wis Lega, antara lain mempertanyakan, yang terjemahannya sebagai berikut. “O, kawan, sudah puaskah kamu, menyanyikan lagu warisan ?”. Tokoh utama dalam cerkak Tiyupan Pedhut Anjasmara menolak penilaian baik terhadap karya Wicara Keras, Darmasunya, dsb.. Penilaian baik itu dianggap sebagai tiyupan pedhut atau ‘ hembusan kabut’ yang berkonotasi negatif (Hutomo, 1993: 2002-2004). Dewasa ini dalam pengajaran sastra di sekolah-sekolah tampak bahwa penjenisan sastra diterapkan secara sederhana dengan menekankan bentuk material atau lahiriahnya saja. Secara lahiriah Luxemburg, dkk. (1989) menuliskan bahwa sebuah cerita (fiksi) mengisi seluruh permukaan halaman. Sedang dalam teks drama dijumpai banyak bidang putih, khususnya bila pembicaranya ganti. Nama-nama pelakunya dicetak secara khusus sehingga meyakinkan sebagai drama. Dalam hal puisi pun biasanya halaman tidak terisi penuh (larik-lariknya tidak panjang) dan bait-baitnya dipisahkan oleh bidangbidang putih atau larik-larik kosong. Perbedaan antara roman dan novel ditentukan panjangnya teks atau jumlah kata. Luxemburg, dkk. (1989) juga membagi bab-bab dalam bukunya menjadi teks-teks naratif, teks-teks drama dan teks-teks puisi. Teks naratif sering disebut juga jenis fiksi yang biasanya berbentuk prosa atau disebut prosa fiksi. Luxemburg membatasi teks naratif ialah semua teks yang tidak bersifat dialog 17 dan yang isinya merupakan suatu kisah sejarah, sebuah deretan peristiwa. Teksteks drama ialah semua teks yang bersifat dialog-dialog dan yang isinya membentangkan sebuah alur. Sedang teks-teks puisi ialah semua teks monolog yang isinya tidak pertama-tama merupakan sebuah alur. Bila ditinjau secara pragmatis, ada keunggulan masing-masing jenis tersebut. Jenis prosa atau gancaran, memiliki keunggulan-keunggulan komunikatif, antara lain: lugas dan jelas. Lugas, maksudnya secara umum lebih banyak menggunakan kosa kata sehari-hari sehingga lebih mudah untuk dicerna pembaca. Sedang jelas, maksudnya secara umum lebih banyak menggunakan stuktur gramatikal sesuai dengan standar bahasa formal yang berlaku. Kedua sifat gancaran tersebut berimplikasi lebih lanjut pada sifat yang lebih komunikatif. Artinya, sangat memungkinkan bagi pembaca untuk memahami isinya dalam waktu yang relatif singkat. Pembaca mengerti dan memahami hanya dengan sekali baca. Jenis puisi meniliki keunggulan-keunggulan estetis, yakni antara lain menekankan pemilihan diksi yang padat, bebas dan indah. Padat, artinya bahwa dalam satu kata puisi dapat menampung keluasan makna imajinatif sehingga menawarkan pemaknaan yang relatif sangat dalam. Bebas, maksudnya tidak sangat terikat oleh kaidah-kaidah linguistis, seperti halnya kaidah gramatikal. Larik-larik puisi tidak harus berstruktur seperti kalimat formal, ada subyeknya ada predikatnya dan seterusnya. Indah, maksudnya menekankan pentingnya segala unsur yang bernilai keagungan seni. Ketiga sifat puisi tersebut secara estetis membuatnya tidak kaku tidak membosankan dan kaya akan makna. Jenis drama menekankan dialog dan lakuan yang mengarah pada konflik para pelakunya. Jenis ini tentu saja memiliki keunggulan aksi dramatik. Artinya, jenis drama lebih banyak menawarkan gerak laku dan pembicaraan efektif yang berisi alur cerita. Dengan demikian pengekspresiannya diaktualisasikan dalam pertunjukan. Dari segi cara sarana penuangan idenya atau cara penyebarannya, karya sastra dapat dibedakan menjadi sastra tulis, yakni menggunakan sarana tulisan, dan sastra lisan, yakni yang disebarkan secara lisan atau dari mulut ke mulut. 18 D. Pendekatan terhadap Karya Sastra Karya sastra pada dasarnya menyangkut berbagai aspek, yakni tentang karya sastra itu sendiri (segi intrinsik) dan berbagai aspek kehidupan (segi ekstrinsik). Oleh karena itu perihal teori sastra juga mencakup aspek yang sangat luas, yakni seluas ilmu yang ada dalam kehidupan ini yang tercakup dalam ilmu kebudayaan secara umum. Dengan demikian, teori sastra berhubungan dengan semua unsur kebudayaan, yakni bahasa, kesenian, ilmu pengetahuan, kemasyarakatan, ekonomi, teknologi, dan religi. Pada mulanya, teori sastra setidak-tidaknya menyangkut tiga hal, yakni teori moral, teori formal dan teori sosial. Teori moral berkembang dalam sastra sejak semula. Secara moral, karya sastra bernilai dalam rangka pemaknaan pada pengalaman pribadi perorangan untuk membangun moralitasnya. Bagi ahli moral, nilai karya sastra tidak semata-mata terletak pada estetikanya, melainkan fungsi moralnya. Pada akhirnya nilai karya sastra ditentukan oleh sumbangannya kepada pengalaman orang dalam perkembangan moralnya pada keseluruhan hidupnya, dalam rangka kemajuan dan kedamaian dalam sejarah suatu masyarakat. Teori formal muncul lebih belakangan, lebih kompleks, dan lebih canggih. Dengan teori formal, sastra dapat diungkapkan secara beragam bentuk, berjenis-jenis. Teori formal juga telah merambah ke arah estetika sastra. Karya sastra dipandang sebagai struktur-struktur tertentu dengan fungsinya masingmasing. Teori formal mengandaikan pentingnya struktur karya sastra itu, sehingga pada tataran tertentu menolak hubungan karya sastra dengan dunia di luar karya sastra yang bersangkutan. Pada tataran tertentu, secara ideal karya sastra adalah otonom, terlepas dari pengarang dan kehidupannya, terlepas dari sejarah kemunculannya, terlepas dari lingkungan sosialnya. Teori sosial menganggap sastra adalah gejala sosial. Teori ini mengacu pada landasan sosial yang melatar-belakangi munculnya suatu karya sastra, hubungan karya sastra dengan kelompok sosial tertentu, hingga fungsi karya sastra dalam kehidupan kelompok sosial tertentu. Pada tataran tertentu teori ini sampai pada teori komunikasi, yakni karya sastra sebagai sarana komunikasi. 19 Pengarang menulis karya sastra untuk mengkomunikasikan segala ide atau gagasan serta segala amanatnya, yang disampaikan kepada masyarakat. Pada perkembangan selanjutnya, muncul berbagai pendekatan, antara lain yang dicetuskan oleh Abrams, suatu teori sastra menyangkut empat situasi karya sastra secara menyeluruh, yakni pencipta (pengarang), karya sastra itu sendiri, alam semesta, dan pembaca (Teeuw, 1984: 50). Dengan demikian teori sastra di samping membicarakan karya sastra itu sendiri yang berhubungan dengan struktur karya sastra dan makna karya sastra; juga berhubungan dengan latar belakang yang menyangkut alam dan kehidupan manusia di sekitar munculnya karya sastra; berhubungan dengan pengarang dan proses penciptaan karya sastra; dan berhubungan dengan pribadi pembaca atau lingkungan masyarakat pembaca. BAB II KHASANAH SASTRA JAWA A. Pandangan Filosofis sebagai Bingkai Sastra Jawa Di atas telah disinggung bahwa karya sastra (Jawa) sedikit atau banyak akan terikat oleh konvensi yang ada pada masing-masing jenis sastra yang bersangkutan. Konvensi yang ada dalam setiap jenis sastra Jawa, tentu saja tidak akan bertentangan dengan idealisme filosofis yang dimiliki oleh masyarakat Jawa. Memang tidak mudah menangkap idealisme filosofis Jawa yang mana yang tercermin dalam tiap-tiap jenis sastra, bahkan tiap-tiap teks sastra. Namun 20 demikian, setidak-tidaknya dinamika kebudayaan Jawa secara luas mestinya tetap diacu dalam penciptaan teks-teks sastra baru maupun dalam pemaknaannya. Dengan pandangan di atas, setidak-tidaknya harus ditekankan pengertian adanya pengaruh dari kebudayaan-kebudayaan besar yang telah masuk dalam eksistensi kebudayaan Jawa dari waktu ke waktu. Adanya budaya animismedinamisme sebagai dasar kehidupan budaya nenek moyang, pengaruh budaya Hindu-Budha yang saat ini masih tercermin dalam berbagai cerita wayang purwa, pengaruh budaya Islam yang kemudian tercermin dalam sastra suluk, sastra tuntunan, wayang menak, dsb., serta pengaruh budaya Barat yang kemudian tampak pada kehidupan sastra Jawa modern, hingga pengaruh kompleksitas nasionalisme yang kemudian memunculkan sastra-sastra Jawa bervisi Indonesia, adalah contoh-contoh yang harus dicermati. Demikian pula pengaruh globalisasi yang pada akhirnya membawa dampak pada berbagai kehidupan berkesenian, termasuk bersastra Jawa. Menurut A. Teeuw (1984: 101), sastra dan seni selalu berada dalam ketegangan antara aturan dan kebebasan, antara konvensi dan inovasi. Dengan demikian, kehidupan sastra Jawa akan selalu menjadi anak bangsa (Jawa) sekaligus juga menjadi anak jamannya. Artinya, nilai-nilai budaya Jawa yang merupakan hasil perenungan dan pengendapan dari berbagai benturan budaya asli dan asing, akan selalu mendasari penciptaan karya sastra Jawa, sekaligus juga terjadi tawar-menawar dengan berbagai budaya yang berlaku secara up to date di Jawa. Tidak mustahil bila beberapa waktu yang lalu muncul ketoprak dengan bahasa Indonesia, tetapi secara substantif tetap berisi budaya Jawa secara kental. Sebaliknya, karya-karya yang berbau postmodernisme hingga dekonstruksi juga mewarnai karya-karya sastra Jawa, seperti tampak pada berbagai sastra cerkak, ketoprak plesetan, dsb. B. Sastra dan Bahasa Jawa Pembicaraan mengenai sastra Jawa, pada dasarnya membicarakan karya sastra yang berbahasa Jawa, baik bahasa Jawa Kuna, Jawa Pertengahan, maupun bahasa Jawa baru, dengan latar belakang pengaruh kebudayaan tertentu dan dalam jenis sastra dan bentuk sastra tertentu. 21 Telah disinggung pada bab sebelumnya bahwa secara historis atau secara vertikal sastra Jawa menggunakan media bahasa Jawa yang meliputi bahasa Jawa Kuna, Jawa Pertengahan dan Bahasa Jawa Baru. Sedang secara horizontal, terdapat bahasa standar atau baku dan bahasa dialek tertentu. Dewasa ini setidaktidaknya terdapat bahasa Jawa dialek Yogyakarta dan Surakarta yang dianggap sebagai bahasa standar, bahasa dialek Banyumasan dan bahasa dialek Jawa Timuran. Dalam rangka karang-mengarang, pada umumnya menggunakan bahasa standar, namun juga tidak tertutup kemungkinan penggunaan dialek tertentu sebagai warna lokal (local colour) yang memunculkan efek suasana cerita menjadi semakin hidup. Bahkan karya sastra Jawa dengan pengantar dialek tertentu akan memperkaya khasanah sastra Jawa. Bahasa Jawa Kuna dalam arti luas, dapat dibedakan dalam dua istilah, yakni bahasa Jawa Kuna dan bahasa Jawa Pertengahan dengan ciri-cirinya masing-masing. Bahasa Jawa Kuna, di samping dipakai dalam beberapa bentuk prosa, dipakai dalam bentuk puisi kakawin. Sedang bahasa Jawa Pertengahan, di samping dipakai dalam beberapa bentuk prosa, juga dipakai dalam bentuk puisi kidung. Menurut Poerbatjaraka (1964: 68), penggunaan bahasa Jawa Kuna dalam kehidupan sehari-hari hanya sampai pada waktu sebelum berdirinya kerajaan Singasari. Setelah itu, orang sudah menggunakan bahasa Jawa Pertengahan. Pada jaman Majapahit, bahasa Jawa Pertengahan sudah menjadi bahasa sehari-hari dan bahasa umum. Namun demikian dalam bahasa sastra, para pujangga Majapahit masih menggunakan bahasa Jawa Kuna, seperti dalam Nagarakretagama, Arjunawijaya, dan sebagainya, bahkan tradisi penulisan sastra dengan bahasa Jawa Kuna masih dapat ditemukan di Bali pada jaman modern ini. Adapun menurut Zoetmulder (1983: 29-37), istilah bahasa Jawa Kuna dan bahasa Jawa Pertengahan bukanlah semata-mata pembagian secara kronologis, bahwa Jawa Pertengahan berawal dari bahasa Jawa Kuna. Bahasa Jawa Pertengahan tidak menjembatani bahasa Jawa Kuna dengan bahasa Jawa Modern. Pembagian kronologis berdasarkan bahasa sering merupakan landasan yang rapuh, yang harus dipertimbangkan lebih jauh berdasarkan bukti-bukti lain. 22 Zoetmulder mengetengahkan fakta kerapuhan bukti linguistis atau evidensi intern itu antara lain sebagai berikut. C. Kitab Siwaratrikalpa (Lubdhaka) yang semula ditafsirkan sebagai hasil dari bagian pertama abad ke-13 atau awal Singasari, tetapi penelitian terakhir membuktikan bahwa kitab itu berasal dari bagian kedua abad ke15 atau akhir Majapahit. Jadi terpaut dua setengah abad. 2) Bukti yang lain bahkan di Bali beberapa kakawin merupakan hasil penulisan abad ke-19. 3) Dalam sastra kidung pun cara penulisan raja pelindung pada bagian introduksi atau bagian epilog yang sering ada dalam tradisi penulisan kakawin, tidak terjadi pada jenis kidung, sehingga kepastian umurnya sangat lemah. Disamping itu sastra kidung tampak bukan meneruskan tradisi Jawa Kuna. 4) Terdapat bukti pada sejumlah piagam dari periode Majapahit paling tua, bagian kedua abad ke-14, yang berbahasa Jawa Pertengahan dan mendekati bahasa Jawa Modern. 5) Terdapat bukti dua karya tentang agama Islam yang berbahasa Jawa Modern yang dibawa oleh pelayaran Belanda dan dihadiahkan ke perpustakaan Universitas Leiden pada tahun 1597. Dua karya yang berbahasa Jawa Modern itu tentu saja ditulis sebelum tahun 1597, yakni pada abad ke-16. Dengan demikian pada abad ke-16 sebenarnya sudah terdapat tiga jenis bahasa sekaligus, yakni Jawa Kuna, Jawa Pertengahan dan Jawa Modern. Namun demikian hingga kini belum jelas pemetaannya, di daerah bagian mana atau situasi seperti apa berlaku bahasa Jawa Kuna, berlaku bahasa Jawa Pertengahan atau bahasa Jawa Baru. Secara umum dapat dikatakan bahwa daerah tertentu memiliki latar belakang budaya tertentu yang sering berbeda dengan daerah lain. Dalam bahasa Jawa hal itu tercermin dalam konsep desa mawa cara negara mawa tata, yang berarti ‘desa mempunyai tata caranya sendiri-sendiri dan negara juga mempunyai aturan masing-masing’. Bila memungkinkan untuk diketahui bahwa suatu karya sastra berasal dari daerah tertentu dan pada waktu tertentu, maka berbagai hal di dalamnya akan lebih memungkinkan untuk dikaji dalam hubungannya dengan latar belakang budaya daerah yang bersangkutan. 23 Masing-masing dari ketiga jenis bahasa Jawa di atas, juga memiliki karakteristik yang khas, yang berhubungan dengan karakteristik sosial tertentu dan estetikanya masing-masing. Sebagai misal, bahasa Jawa Kuna, dalam banyak kasus menekankan aspek keindahan (kalangwan) dalam hubungannya antara penyair dan karya sastranya dengan raja, dewa dan lingkungan alam, baik alam dalam pola pikir di India maupun di Jawa. Bahasa Jawa Pertengahan, pada beberapa hasil sastra kidung tampak menekankan aspek historis dan penokohan pahlawan-pahlawan tertentu, serta kondisi lingkungan sosial di Jawa terutama dari Kerajaan Majapahit. Sedang pada bahasa Jawa Baru, sebagiannya merupakan penulisan kembali karya-karya sastra lama, sebagiannya lagi merupakan karya baru yang bernuansa Islami atau lingkungan sosial pada jaman Pesisiran, atau karya-karya jaman Mataram. Sebagian lagi merupakan karya modern yang telah mendapat pengaruh Barat dengan menekankan kehidupan keseharian. Yang perlu juga dicatat adalah bahwa dalam bahasa Jawa Baru ditekankan adanya undha-usuk, yakni tataran kebahasaan dalam hubungannya dengan status pembicara terhadap orang yang diajak berbicara. Dalam konteks sosial, penggunaan bahasa jawa Baru telah membantu pengkajian sastra untuk merekonstruksi struktur sosial yang ada dalam karya sastra dalam hubungannya dengan struktur sosial yang sesungguhnya dalam realita kehidupan orang Jawa. Di samping hal-hal di atas, dalam hubungannya dengan jenis karya sastra Jawa, sering kali dijumpai jenis-jenis sastra Jawa tertentu yang banyak menekankan penggunaan bahasa Jawa tertentu pula. Dalam sastra wayang, misalnya, meskipun muncul dengan bahasa Jawa Baru pada dekade belakangan, namun penggunaan bahasa Jawa Kuna dan bahasa Jawa Pertengahan masih relatif dominan. Dalam sastra suluk atau wirid dan sastra Islami lainnya, termasuk sastra Pesisiran, tentu saja penggunaan bahasa dengan pengaruh bahasa Arab akan tampak dominan. Sedang dalam sastra Jawa yang berjenis novel, novelet cerpen (cerkak), geguritan, dan sandiwara modern, penggunaan bahasa Jawa Baru sehari-hari tampak paling dominan. Dalam hubungannya dengan bentuk puisi tembang, di sana-sini banyak menggunakan kosa kata yang disesuaikan dengan kepentingan kaidah tembang 24 yang bersangkutan, sehingga pada umumnya banyak menggunakan kosa kata bahasa yang khas untuk tembang. Sebagai contoh kata Mataram sering diganti dengan kata Mentawis atau Matarum atau Ngeksiganda demi mendapatkan bunyi vokal akhir baris (guru lagu) atau jumlah suku kata pada baris tertentu (guru wilangan) yang sesuai. Demikian pula baris Anoman sampun malumpat dapat saja dibalik menjadi Anoman malumpat sampun, juga demi ketentuan guru lagu, dsb. Dalam hubungannya dengan pengkajian dan pemaknaan sastra, khususnya sastra Jawa, tentu saja hal-hal di atas tidak boleh diabaikan, mengingat makna karya sastra tidak terlepas dari latar belakang sejarah karya sastra yang bersangkutan, termasuk sistem kebahasaan masing-masing. Meskipun demikian, pengungkapan tentang latar belakang sejarah karya sastra bukanlah hal yang sederhana dan menjadi persoalan tersendiri dalam sejarah sastra Jawa, karena berbagai kendala yang melekat pada karakteristik jenis-jenis sastra Jawa tertentu. C. Tradisi Alih Bahasa dan Menyalin Teks Dalam kehidupan khasanah sastra Jawa, masalah penciptaan sastra juga diwarnai oleh tradisi alih bahasa dan tradisi menyalin teks. Tradisi alih bahasa adalah tradisi menterjemahkan teks, yakni terjadi khususnya pada penerjemahan teks-teks sastra berbahasa Sansekerta ke dalam bahasa Jawa Kuna, Jawa Kuna ke bahasa Jawa Baru, bahasa Melayu ke bahasa Jawa Baru, dsb. Tradisi menyalin teks bisa terjadi dari huruf Jawa ke huruf Jawa, dari huruf Arab ke huruf Jawa, dari huruf Arab ke huruf Latin, dari huruf Jawa ke huruf Latin, atau sebaliknya dari huruf Latin ke huruf Jawa. Yang menjadi catatan dalam rangka teori sastra Jawa adalah bahwa dalam kedua tradisi tersebut di atas sering terjadi empat macam hasil, sebagai berikut. Pertama, penerjemah atau penyalin sangat mampu dan setia menerjemahkan atau menyalin, sehingga hasilnya sama dengan teks induknya. Kedua, penerjemah atau penyalin mampu dan setia menerjemahkan atau menyalin, tetapi oleh karena faktor manusiawi, terjadi kesalahan dan hasilnya berbeda dengan teks induknya. Ketiga, penerjemah atau penyalin memang sengaja membuat terjemahan atau 25 salinannya berbeda dengan teks induknya, oleh karena tujuan tertentu. Keempat, penerjermah atau penyalin kurang atau tidak mampu melaksanakan tugasnya, sehingga hasilnya berbeda dengan teks induknya. Dengan kejadian tersebut, menjadikan teks-teks sastra Jawa sebagai ladang luas dan subur bagi pengkajian filologi.. Hasil dari pengkajian tersebut, di samping mendapatkan teks aslinya, mendapatkan teks edisi kritis, juga menghasilkan pengetahuan tentang visi dan misi penerjemah atau penyalin. Dalam rangka pemaknaan karya sastra, sangat mungkin didapatkan maknamakna yang baru dari teks terjemahannya atau teks salinannya, yang berbeda dengan makna dari teks aslinya. Dalam hubungannya dengan hal di atas, Teeuw (1984: 216) mencatat bahwa dalam sastra Jawa proses saduran atau penjarwaan, khususnya di Surakarta dan Yogyakarta, perlu mendapatkan perhatian yang serius, yakni dalam rangka resepsi sastra, karena akan memberi sumbangan yang sangat penting terhadap sejarah sastra dan lebih luas pada pengetahuan mengenai konteks sosio-budaya tertentu. D. Tradisi Lisan dan Tulisan Dalam tradisi sastra Jawa, seperti juga tradisi-tradisi yang lain, di samping dalam tradisi tulis, juga diwarnai tradisi penyebaran sastra melalui tradisi lisan. Tradisi lisan merupakan tradisi yang ditularkan dari mulut ke mulut secara turun temurun. Dalam tradisi sastra Jawa, antara tradisi lisan dan tulisan berjalan bersama, sehingga sering sekali terjadi saling mempengaruhi. Sebagai contoh, tradisi wayang purwa dan seni kethoprak, yang semula lebih berkembang dalam tradisi lisan, akhirnya juga berkembang dalam tradisi tulis. Namun demikian sebagian hasil sastra tulis kemudian juga berkembang dalam tradisi lisan, seperti tradisi wayang purwa dan kesenian kethoprak tersebut. Tradisi lisan memiliki karakteristik luwes, sangat mampu menyesuaikan situasi dan kondisi di mana ia berkembang. Oleh karena itu perubahan demi perubahan bisa terjadi begitu saja dengan cepatnya. Hal ini berbeda dengan tradisi tulisan yang mencatat segala yang ada dengan lebih statis, bisa dibaca dalam kondisi yang relatif sama dalam jangka waktu yang lama. Dengan kata lain 26 tradisi tulis telah membakukan eksistensi teksnya. Apabila suatu tradisi lisan berkembang dalam bentuk tulisan maka pada saat pertama penulisan itu, berbagai perubahan yang telah terjadi dalam tradisi lisan sebelumnya, menjadi tertulis dan cenderung menjadi baku. Dengan demikian dalam tradisi tulis semacam ini dapat menjadi semacam titik-titik stasioner perubahan. Dalam sastra Jawa hal tersebut mungkin juga terjadi pada persebaran teks-teks sastra tertentu, khususnya pada lakon-lakon wayang purwa dan dongeng-dongeng atau legenda-legenda tertentu. Dengan demikian perlu dicermati lebih jauh, pemaknaan karya sastra Jawa dalam hubungannya dengan persebaran melaui tradisi lisan dan tulisan yang telah saling mempengaruhi. E. Sang Kawi, Pujangga atau Pengarang Sastra Jawa Penamaan pujangga atau pengarang pada dasarnya dibedakan dalam kemampuannya, masa hidupnya, dan popularitasnya. Pujangga hidup pada jaman kekuasaan para raja Jawa. Khususnya dalam sastra Jawa Kuna, penyair biasa disebut Sang Kawya atau Ra Kawi atau Sang Kawi, sedang lembaganya sering disebut Para Kawi yang mungkin bisa disejajarkan dengan ‘Jawatan Kebudayaan dan Kesusasteraan’. Istilah kawi sendiri bisa berarti ‘seorang penyair’ tetapi juga bisa berarti lebih luas, yakni ‘seseorang yang mahir atau mempelajari buku-buku’ atau ‘seseorang yang mahir dalam kitab-kitab suci’ (Zoetmulder, 1983: 184-186). Dalam istilah Jawa, pujangga juga sering disebut kawitana, kawiwara, atau kawiswara. Menurut Padmosoekotjo (tt, jld I: 13) dan Padmawarsita (dalam Serat Ranggawarsita, Cod. Or. 6467: 12), pujangga harus memiliki delapan macam kemampuan, yakni sebagai berikut. 1). Paramengsastra, yakni ahli dalam bidang sastra dan bahasa, menguasai tentang bunyi, rasa dan makna bahasa sastra. 2). Paramengkawi, yakni ahli mencipta sastra atau mengarang, terutama dalam penggunaan bahasa Kawi (Bahasa Jawa Kuna dan bahasa yang sering dipakai oleh para Pujangga yang sering disebut Kawi Miring). 3). Awicarita, yakni pandai mendongeng atau bercerita dengan menarik dan dapat menjadi pedoman hidup manusia. 27 4). Mardawa lagu, yakni pandai dan halus dalam hal membuat tembang dan gendhing. 5).Mardawa basa, atau mardi basa yakni pandai menggunakan bahasa yang menyenangkan, yang menyentuh perasaan, membangkitkan rasa kasih, dan sebagainya. 6). Mandraguna, yakni ahli dalam cipta sastra dan dalam hubungannya dengan hal kesaktian dan supranatural. 7). Nawung kridha, yakni halus budi dan perasaannya hingga mampu membaca perasaan orang lain. 8). Sambeguna, yakni bijaksana atau baik budi. Dalam hal kata pujangga, ada kemungkinan berasal dari kata empu janggan yang berarti ‘tuan guru’ seperti yang terdapat dalam kitab Pararaton yang antara lain menyebutkan Empu Janggan ing Sagenggeng yang berarti ‘tuan guru di Sagenggeng’ (Asia Padmopuspito, tt: 18). Namun dimungkinkan juga berasal dari bahasa Sansekerta, yakni kata bhujangga yang berarti ‘ular’ atau ‘naga’. Tidak mengherankan bahwa tanda tangan R. Ng. Ranggawarsita pada beberapa naskah asli karyanya, berupa gambar seekor naga atau menyerupai naga. Ranggawarsita sendiri memang menyebut dirinya sebagai pujangga. Hal ini antara lain disebut dalam karyanya Serat kalatidha pada bait I pupuh Sinom, sebagai berikut. Wahyaning harda rubeda / Ki Pujangga amengeti / mesu cipta mati raga / mudhar warananing gaib / ananira sakalir / ruweding sarwa pekewuh / wiwaling kang warana / dadi badhaling Hyang Widdi / amedharken paribawaning bawana. Oleh karena kraton, khususnya Istana Kasunanan Surakarta tidak mewisuda pujangga lagi setelah Ranggawarsita, konon pada umumnya kalangan pengamat sastra Jawa juga menyebutkan bahwa pujangga terakhir adalah R.Ng. Ranggawarsita, dan setelah itu orang sering hanya menamakan sebagai pengarang saja. Adapun, saat ini kata pengarang sering dibubuhkan untuk menyebutkan nama pengarang sastra Jawa Modern atau sastra Jawa gagrag anyar. 28 Penghargaan terhadap pujangga, tentu saja berpengaruh terhadap resepsi masyarakat pada makna dan nilai karya sastra. Pada sebagian masyarakat yang memegang keyakinan akan keunggulan kemampuan pujangga dan hasil karya sastranya, akan cenderung menilai karya sastra Jawa modern, yakni karya pengarang yang bukan pujangga, nilainya tidak akan melebihi makna karya sastra lama yang merupakan karya para pujangga. Hal ini tentu harus dicermati secara hati-hati dengan mendasarkan pada kekhasan karya sastra masing-masing dan kekhasan bidang kajian masing-masing. Misalnya saja dalam rangka pendekatan pragmatik, tentu harus mengingat filosofi nut jaman kelakone, empan papan, dsb, sehingga parameter penilaiannya akan berbeda-beda. Di depan nama para penyair Jawa Kuna sering digunakan sebutan empu. Dalam sejarah sastra Jawa Kuna antara lain dikenal pujangga yang bernama Empu Kanwa (menulis Arjunawiwaha), Empu Sedah dan Empu Panuluh (bersama-sama menulis Bharatayuddha), Empu Panuluh (sendiri menulis Hariwangsa, Gatotkacasraya), Empu Triguna (menulis Kresnayana), Empu Monaguna (menulis Sumanasantaka), Empu Tantular (menulis Arjunawijaya dan Sutasoma), Empu Tanakung (menulis Lubdhaka atau Siwaratrikalpa), Empu Prapanca (menulis Nagarakertagama), dan Empu Dharmaja (menulis Smaradahana). Pada sastra Jawa Kuna, khususnya dalam kakawin, penyebutan nama penyairnya sering terdapat dalam bagian manggala yakni bagian introduksi atau prolog, atau kemungkinan lain terdapat di bagian epilog, yang biasanya juga untuk menyebut-nyebutkan nama raja pelindungnya serta dewa yang dipujanya. Dalam sastra Jawa Pertengahan tradisi yang demikian itu tidak terjadi. Nama penulis kidung (Jawa Pertengahan) harus dicari pada bagian lain. Sering kali baik dalam kakawin maupun dalam kidung, nama penyairnya harus ditentukan dengan membandingkan pada karya-karya yang lain atau dari bukti-bukti lain. Dalam satra Jawa Baru, penyebutan empu tidak lagi lazim. Pada jaman Islam (Jaman Demak dan Pajang), antara lain tersebut nama Sunan Bonang dalam Suluk Wujil, Sunan Panggung sebagai penulis Suluk Malang Sumirang, dan Pangeran Karanggayam sebagai penulis Nitisruti, dsb. 29 Pada jaman Mataram diantaranya dikenal para pencipta sastra sebagai berikut. Raja Sultan Agung menulis Nitipraja dan Sastragendhing. Pangeran Adilangu menulis Babad Pajajaran, Babad Majapahit, Babad Pajang, dan Babad Mataram. Carik Bajra menulis Serat Damarwulan dan Babad Kartasura. Ranggadjanur menulis Pranacitra dan Dewi Rengganis. Sunan Pakubuwana IV menulis Wulang Reh dan Wulang Sunu. Sunan Pakubuwana V menulis Serat Centhini. R.Ng. Yasadipura I (Yasadipura Tus Pajang) menulis Cebolek, Babad Pakepung, Babad Giyanti, Serat Rama, Serat Dewaruci, Ambiya, Tajusalatin, Serat Menak, Joharmanik, Nawawi, Bustam, Serat Sewaka, Serat Panitisastra, dan Serat Lokapala. R.Ng. Yasadipura II (R.T. Sastranagara) menulis Sasanasunu dan Wicarakeras. Ng. Sindusastra menulis Arjunasasrabau, Partayagnya Srikandhi Maguru Manah dan Sumbadra Larung. (lakon Partakrama), K.G. Mangkunegara IV menulis Wedhatama, Buratwangi, Sendhon Langenswara, Panembrama, Tripama, Salokatama, Wirawiyata, dan Rerepen. R. Ng. Ranggawarsita menulis Jayengbaya, Widyapradana, Hidayatjati, Jayabaya, Purwakaning Serat Pawukon, Pustakaraja Purwa, Rerepen sekar Tengahan, Sejarah Pari Sawuli, Uran-uran Sekar Gambuh Warni Pitu, Panitisastra, Bratayuda Jarwa Sekar Macapat, Cakrawati, Sidawakya, Pawarsakan, Darmasarana, Yudayana, Budayana, Pustakaraja Madya, Ajipamasa, Witaradya, Ajidarma, Pambeganing Nata Binathara, Kalatidha, Sariwahana, Purusangkara, Wedhayatmaka, Wedharaga, Cemporet, Wirid, Paramayoga, Jakalodhang, Sabdatama, dan Sabdajati. P. Kusumadilaga menulis Serat Bale Si Gala-gala, Jagal Bilawa, Kartapiyoga (Endhang Werdiningsih), Jaladara Rabi, Kurupati rabi, Serat sastramiruda, dan Serat Partadewa Setelah abad XX, antara lain tercatat para penulis sebagai berikut. Ki Padmasusastra menulis Tatacara, Pathibasa, Paramabasa, Warnabasa, Urabsari, Durcaraharja, Rangsang Tuban, Kandhabumi, Kabar Angin, dan Prabangkara. 30 M. Ng. Mangunwijaya menulis Purwakanthi, Trilaksita, Jiwandana, Asmaralaya, Lambangpraja, dan Wuryalocita. R Ng. Sidupranata menulis Sawursari. Ng. Sastrakusuma menulis Dongeng Kuna R. T. Tandhanagara menulis Pepiling dan Baruklinthing. M. Suryasuparta (K.G. Mangkunegara VII) menulis Kekesahan saking Tanah Jawi dhateng Negari Walandi, dan Serat Pakem Pedhalangan Ringgit Purwa. R.M. Sulardi menulis Serat Riyanta. Bratakesawa menulis Candrasangkala. Wiradad menulis Calonarang. M. Sukir menulis Abimanyu Kerem. Sastrasutarna menulis Bancak Dhoyok Mbarang Jantur. Mas Sumasentika menulis Buta Locaya. (Padmosoekotjo, t.t, jld. II: 152-153). Mengenai para pengarang dan hasil karya sastra Jawa modern, agar lebih lengkap dapat dilihat juga dalam J.J. Ras, (1979: 1-30). Khususnya pada karya sastra Jawa Kuna, Pertengahan dan beberapa karya sastra Jawa Baru yang termasuk tua (hingga karya Jaman Mataram), ditemukan naskah-naskah sastra yang tidak diketahui siapa pengarangnya. Hal ini sebagiannya mungkin merupakan kesengajaan pengarang yang memang tidak mau menyebutkan atau mencantumkan namanya pada karya sastranya itu. Namun demikian sebagiannya mungkin pada bagian-bagian yang biasanya untuk menyebutkan nama pengarangnya, telah rusak dan tak terbaca lagi. Dalam tradisi kepenulisan karya sastra Jawa, disamping pujangga dan pengarang, seperti telah disinggung di atas, masih ada lagi yakni penulis, penyalin atau penurun atau penerjemah, karena terdapat tradisi penyalinan teks dan terdapat tradisi penulis sebagai suruhan raja atasannya. Dalam sejarah sastra Jawa banyak sekali hasil karya sastra yang merupakan salinan atau turunan atau saduran atau terjemahan (jarwa) dari teks-teks sastra yang sudah ada sebelumnya. Namun ada juga yang mengarang atau menyalin dalam rangka suruhan pihak lain. Dalam hal menyalin, sebagian penyalin bersikap sangat setia dalam mempertahankan keaslian teks sehingga perbedaan teks asli dengan salinannya sedikit. Namun demikian sebagian yang lain bersikap kritis dengan menghapus, merubah atau mengganti sebagian teks yang disalinnya, sebagai tanggapan terhadap teks yang disalinnya. 31 Dalam tradisi sastra lisan Jawa yang ditularkan dari mulut ke mulut, hampir semua karya sastra lisan akhirnya tidak diketahui siapa pengarangnya (anonim). Dalam hal ini terdapat dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, karya tersebut menjadi milik bersama masyarakat Jawa tetentu atau masyarakat Jawa pada umumnya. Kemungkinan kedua, muncul sebagai cerita lisan dari mulut-ke mulut bahwa suatu hasil sastra adalah karya tokoh masyarakat tertentu. Sebagai contoh, hingga sekarang jenis-jenis Tembang Macapat tidak diketahui secara pasti siapa penciptanya, namun telah menjadi legenda bahwa beberapa jenis Tembang Macapat merupakan hasil ciptaan para wali atau raja tertentu. Tradisi untuk tidak menyebutkan nama pengarang bahkan lalu menjadi ciri khas sastra lisan, khususnya sastra lisan Jawa. Berbeda dengan hal itu, dalam sastra tulis banyak yang dengan sengaja menuliskan namanya, yang dalam tradisi Jawa disebut sastra miji, atau milik pribadi tertentu. Dalam hal nama pengarang, ada nama asli dan bukan. Sejumlah pengarang mencoba mengabadikan namanya justru melalui nama samaran. Nama samaran, pada karya sastra Jawa Modern yang berbentuk prosa, pada umumnya dituliskan secara jelas, meskipun itu bukan nama sebenarnya. Teknik pemilihan nama samaran sangatlah beragam. Namun demikian sebagiannya masih memungkinkan dikaitkan dengan nama aslinya. Ada yang memilih nama samaran dari suku-suku kata awal dari nama aslinya, misalnya Suhawi, nama aslinya Suwanda Hadi Wijana (penulis Rumpakan Suruping Srengenge, dan Barabudur). Ada yang memilih kata terakhirnya, misalnya Srini, nama aslinya Kusrini (penulis Larasati Modern). Any Asmara adalah bernama asli Ahmad Ngubaeni Ranusastraasmara (penulis produktif novel Jawa) . Jayadinama, nama aslinya Jayadiguna. Liasmi bernama asli Ismail (penulis cerpen Jawa Anak Kuwalon). Nama M.W Asmawinangun, banyak yang menerka itu sebagai nama samaran dari M. Ng. Mangun Wijaya (kata asmawinangun berarti ‘nama samaran’). St. Iesmaniasita, nama lengkapnya Sulistyautami Iesmaniasita (penulis geguritan dan cerpenis Jawa). Kamajaya, nama aslinya Karkana Partakusuma. Poerwadhie Atmodihardjo menggunakan banyak nama samaran, seperti Hardja Lawu, Ki Dhalang Dhengklung, Laharjingga, Prabasari, 32 Habramarkata, Sri Ningsih, Sri Djuwarisah, Abang Istar, Kenthus, dsb. Soebagio Ilham Notodidjojo sering menggunakan nama samaran SIN atau Pak SIN, Satrio Wibowo, Anggajali, Damayanti dan Endang Murdiningsih. Soenarno Sisworahardjo menggunakan nama samaran Soesi, S.S., S. Sisworahardjo. Dan sebagainya. Suatu tradisi dalam bentuk puisi, khususnya dalam bentuk tembang, sering kali pengarang mencantumkan nama aslinya maupun nama samarannya, melalui cara penulisan yang disandikan, yakni dengan cara yang dikenal dengan sebutan sandi asma. Kata sandi atau sandya semula berarti ‘sambung’. Kata sandyakala berarti ‘penyambung waktu, yakni antara siang dengan malam’. Namun demikian pada akhirnya kata sandi juga berarti ‘samar’ atau ‘tersamar’ atau ‘rahasia’. Kata asma berarti ‘nama’. Jadi sandiasma maksudnya nama yang tersamar (Padmosoekotjo, tt, jld II: 128). Cara-cara penulisan sandi asma, antara lain sebagai berikut. 1). Setiap suku kata dari nama pengarang dituliskan secara urut, pada suku katasuku kata yang mengawali setiap pupuh tembang. Yang dimaksud pupuh adalah kesatuan bait-bait tembang yang sama jenisnya. Satu judul karya sastra dapat berisi satu pupuh saja, misalnya pupuh Dhandhanggula saja, namun juga dapat berisi banyak pupuh. Satu pupuh dapat terdiri atas satu bait (pada) saja, tetapi pada umumnya terdiri atas banyak bait tembang. Contohnya dalam Serat Ajipamasa, berbunyi Rahadyan Ngabei Ronggawarsita, sebagai berikut. Rasikaning sarkara kaesthi (pupuh Dhandhanggula) Hasasmita wadyanira (pupuh Sinom) Dyan cepu kinon ningali (pupuh Asmaradana) Ngawu-awu ing pamuwus nguwus-uwus (pupuh Pucung) Bela tampaning wardaya (pupuh Pangkur) Iyeg tyas sabiyantu (pupuh Gambuh) Rong prakara pilihen salah setunggal (pupuh Durma) Gagat bangun angun-angun ing praja gung (pupuh Megatruh) Warnanen tanah ing Sabrang (pupuh Pangkur) Sira Sang Prabu kalihnya (pupuh Girisa) 33 Talitining wong abecik (pupuh Asmaradana). 2). Setiap suku kata dari nama pengarang dituliskan secara urut, pada suku katasuku kata yang mengawali setiap bait, dalam beberapa bait tembang, pada pupuh tertentu. Contohnya dalam Serat Sabdatama, pada pupuh Gambuh, tertulis Raden Ngabei Ronggawarsita ing Kedhungkol Surakarta Adiningrat, sebagai berikut. Rasaning tyas kayungyun (bait ke-1) Den samya amituhu (bait ke-2) Ngajapa tyas rahayu (bait ke-3) Beda kang ngaji pupung Ilang budayanipun (bait ke-4) (bait ke-5) Rong asta wus katekuk (bait ke-6) Galap gangsuling tembung Wartaning para jamhur Sidining kalabendu (bait ke-7) (bait ke-8) (bait ke-9) Tatanane tumruntun (bait ke-10) Ing antara sapangu (bait ke-11) Kemat isarat luhur (bait ke-12) Dhungkari gunung-gunung Kolonganing kaluwung Supaya padha emut (bait ke-13) (bait ke-14) (bait ke-15) Rasane wong karasuk (bait ke-16) Karkating tyas katuju (bait ke-17) Tatune kabeh tumurun (bait ke-18) Amung padha tinumpuk (bait ke-19) Diraning durta katut (bait ke-20) Ninggal pakarti dudu (bait ke-21) Ngratani saprajagung (bait ke-22) 3). Setiap suku kata dari nama pengarang dituliskan secara urut, pada suku katasuku kata yang mengawali setiap baris dalam bait-bait tembang tertentu. Contohnya dalam Serat Tapabrata Marioneng, pada bait tembang Kinanthi, tertulis Ki Martasuwita, sebagai berikut. 34 Kinanthi sujanma idhup / Mardi mardaweng palupi / tama tumanem mrih bisa / susulange janma nguni / winuruk ing tapa brata / tatane wirid puniki // 4). Setiap suku kata dari nama pengarang dituliskan secara urut, pada suku katasuku kata yang mengawali baris-baris dan mengawali kata di tengah barisbaris tembang. Contohnya dalam Serat Sandiasma, bait tembang Sinom, berbunyi Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara, sebagai berikut. Kang kocap Jeng Sri Narendra / Gusti titikaning nagri / patih ngengeras pandriya / rancakan angereh budi / dining para wargaji / tinata arja tan ayun / yayah manggung sulaya / kulina nala tan yukti / gagasira rarasan kang tanpa karya // 5). Setiap suku kata dari nama pengarang dituliskan secara urut, pada suku katasuku kata yang tersebar di tengah baris-baris pada bait tembang tertentu, baik dalam hubungannya dengan letak jeda pengambilan napas (pedhotan) tembang maupun tidak, terutama pada awal-awal kata atau akhir-akhir kata. Contohnya dalam Serat Wedhayatmaka, bait tembang Dhandhanggula, berbunyi Radyan Ngabehi Ronggawarsita, sebagai berikut. Tan pantara ngesthi tyas artati / lir winidyan saroseng parasdya / ringa-ringa pangriptane / tan darbe labdeng kawruh / mung ngruruhi wenganing budi / kang mirong ngaruhara / jaga angkara gung / minta luwaring duhkita / haywa kongsi kewran lukiteng kinteki / kang kata ginupita // 6). Setiap suku kata dari nama pengarang dituliskan secara urut, pada suku kata-suku kata yang terdapat dalam satu baris pada tembang tertentu. Misalnya terdapat dalam Serat Kalatidha, pada baris terakhir suatu bait tembang Sinom, berbunyi Ronggawarsita, sebagai berikut. ………… / borong angga suwarga mesi martaya // 7). Nama-nama pengarang di atas dipenggal penulisannya menurut suku katasuku katanya. Hal ini dikarenakan budaya penulisan yang masih umum pada saat itu adalah dengan huruf Jawa. Huruf Jawa pada dasarnya bersifat sylabic yakni satu huruf pada umumnya melambangkan satu suku kata. Jadi 35 wajar bila sandiasma yang ada dengan cara mengurai tiap-tiap suku katanya. Pada perkembangannya ketika budaya menulis dengan huruf Latin sudah sangat memasyarakat, penggalan nama pengarang dalam sandiasma, sebagian berdasarkan huruf-huruf Latin (satu huruf untuk satu fonem). Contoh sandiasma yang berdasarkan huruf Latin berbunyi Sutrisna murid SGB ing Purworejo, dalam empat bait tembang Pangkur, sebagai berikut (Padmosoekotjo, tt, jld. II: 133). Sasat mungkur basa Jawa / Umumira pra mudha jaman mangkin / Tan tumanggah ing panggregut / Ras-arasen nggegulang / Ing ajune basa Jawa mamrih luhur / Sedene duk kuna-kuna / Ngumala lir kala nguni // Apan mangke wus karasa / Mundurira kasusastran Jawi / Upamane trus kabanjur / Rusak budaya Jawa / Ing besuke sapa kang kelangan iku / Datan liya wong Jawa pyambak / Sayekti keduwung wuri // Glagate wus kawistara / getune ing besuk / Bakal rusak kasusasteran Jawi / Iba Nanging yen para mudha / Gelem age nggagahi gumregah nggregut / Padha glis gelem nggegulang / Umum sami mardi yekti // Rahayu budaya Jawa / Wus tartamtu terus lulus lestari / Ora mundur mandar luhur / Rusak kena cinegah / Enggih mangga enggal rumagang yen saguh / Jak-ajak ajeg jumaga / Onjone budaya Jawi // 8). Masih banyak lagi cara penempatan sandiasma, baik yang pemenggalannya berdasarkan suku katanya dalam huruf Jawa maupun berdasarkan huruf Latin. Dalam hubungannya dengan pemaknaan karya sastra, tentu saja pengetahuan siapa pengarangnya menjadi sangat penting, khususnya dalam hubungannya dengan sejarah sastra, sosiologi sastra melalui pengarangnya (termasuk pendekatan struktural genetik), dan dari segi pragmatik. F. Genre Sastra Jawa 36 Dalam sastra Jawa, telah tercatat sejarah yang panjang mengenai penulisan bentuk prosa, yang dimulai dari bahasa Jawa Kuna yakni semenjak adanya sastra Jawa Kuna prosa. Dalam bahasa Jawa Baru tercatat berbagai bentuk gancaran dalam berbagai ragam isi cerita, mulai dari karya-karya historis faktual termasuk laporan kisah perjalanan, historis tradisional (karya-karya babad), hingga karya fiksi murni yang disebut dongeng. Dalam hal puisi Jawa, juga dimulai dari bahasa Jawa Kuna. Sudah disinggung di atas, bahwa dalam sejarah sastra Jawa dikenal puisi dalam bahasa Jawa Kuna yang disebut kakawin dan dalam bahasa Jawa Pertengahan yang disebut kidung. Adapun yang berbahasa Jawa Baru, terdapat kategori puisi tradisional yang berbentuk tembang dan puisi modern yang disebut geguritan. Sedang dalam bentuk drama, jenis drama ini tidak banyak ditulis atau dikupas oleh pakar-pakar sastra Jawa Kuna bahkan juga Sastra Jawa Modern. Agaknya jenis drama yakni teks tertulis atau teks lakon, yang dimaksudkan sebagai pedoman pentas seni drama di panggung, penulisannya belum ditekankan dalam bahasa Jawa Kuna. Dalam bahasa Jawa Baru, khususnya drama tradisional seperti wayang, dikenal bentuk pakem (pedoman untuk pementasan), baik pakem jangkep (pedoman pertunjukan lengkap) maupun pakem balungan (petunjuk pembabakan atau pengadegannya saja). Adapun dalam drama Jawa modern sering disebut dengan istilah sandiwara, terutama sandiwara untuk siaran di radio. Tentu saja penulisan bentuk drama radio berbeda dengan drama untuk pentas. Agaknya tiga jenis inilah (prosa, puisi dan drama) yang secara sederhana dapat dikenali dan tampak berbeda antar masing-masing jenis dalam karya sastra itu. Namun demikian dalam kenyataannya, khususnya dalam sastra Jawa, batasan yang diberikan Luxemburg, dkk. tersebut harus diberi catatan khusus karena adanya bentuk-bentuk yang dasar klasifikasinya ambigu. Misalnya, dalam puisi Jawa tradisional tembang terdapat bentuk-bentuk yang menekankan narasi (puisi naratif), yang merupakan kisah sejarah atau rentetan peristiwa sejarah, yakni misalnya jenis yang dikenal sebagai sastra babad yang, di samping bersifat naratif, kebanyakan ditulis dalam bentuk puisi tradisional tembang, sehingga menjadi ambigu apakah mau diklasifikasikan sebagai puisi atau prosa. Di 37 samping itu, dalam sastra Jawa juga ditemukan bentuk-bentuk puisi tradisional tembang yang di dalamnya menekankan pembagian pembabakan-pembabakan seperti halnya dalam bentuk lakon (drama). Dalam sastra Jawa Kuna terdapat bentuk prosa, baik yang berbahasa Jawa Kuna maupun bahasa Jawa Pertengahan. Disamping itu juga terdapat dua bentuk puisi, yakni kakawin dan kidung. Kakawin berbahasa Jawa Kuna dengan metrum hasil pengaruh dari metrum-metrum di India, sedangkan kidung bermetrum asli Jawa dan berbahasa Jawa Pertengahan. Dalam sastra Jawa Modern tampak pembagian tersebut (prosa, puisi dan drama) banyak diikuti oleh para pengarang. Tidak mengherankan bila banyak bermunculan buku-buku antologi sastra Jawa yang berisi masing-masing jenis tersebut secara terpisah satu dengan jenis lainnya. Misalnya dalam sastra Jawa bermunculan antologi puisi Jawa modern (geguritan), yakni antara lain, Kristal Emas (1994), Mantra Katresnan (2000), Kabar Saka Bendulmrisi (2001), Pagelaran (2003), dsb. Yang berjenis prosa antara lain bermunculan antologi cerkak (cerita pendek Jawa), yakni antara lain Kalimput ing Pedut (1976), Niskala (1993), Bandha Pusaka (2001), dsb. Sedang yang berjenis drama muncul antologi seperti Gapit (1998), Gong (2002), dsb. Dari segi kebahasaannya, seperti telah disinggung di atas, sastra Jawa dapat dibagi menjadi tiga, yakni sastra Jawa Kuna (kakawin dan prosa Jawa Kuna), sastra Jawa Pertengahan (kidung dan prosa Jawa Pertengahan), dan Sastra Jawa Modern (prosa Jawa modern, dan puisi tembang, geguritan, dsb), serta drama Jawa modern. Dari segi sarana penuangan idenya atau sarana sosialisasinya, di samping sastra tulis, sastra Jawa juga mengenal bentuk sastra lisan. Pada perkembangannya, banyak sastra tulis yang kemudian berkembang dalam bentuk sastra lisan. Hal ini misalnya, dalam sastra pedalangan yang pada mulanya menggunakan sumber tertulis Mahabharata dan Ramayana, atau buku-buku pakem pedalangan, kemudian dilisankan dalam bentuk pergelaran oleh dalang. Sebaliknya, juga banyak sastra lisan yang kemudian berkembang dalam bentuk sastra tulis. Hal ini misalnya juga terjadi dalam sastra pedalangan yang bermula 38 dari pergelaran wayang lalu ditulis dalam bentuk pakem (tuntunan) atau bentuk yang lain. Berdasarkan tema atau isi permasalahannya, sastra Jawa mengenal beberapa jenis, antara lain sastra babad, sastra niti, sastra suluk, sastra wayang, primbon, Menak, Panji, dan sebagainya. Hal ini akan diuraikan lebih lanjut pada bab berikutnya. G. Pendekatan terhadap Karya sastra Jawa Dri segi latar belakang munculnya karya sastra, suatu karya sastra berhubungan dengan tradisi atau budaya masyarakat yang melatar belakanginya. Dalam hubungannya dengan sejarah kebudayaan, sastra Jawa telah mendapatkan pengaruh dari berbagai kebudayaan asing, yakni kebudayaan Hindu dan Budha, kebudayaan Islam, pengaruh kebudayaan bangsa Barat, hingga jaman kemerdekaan. Dalam perkembangannya, sastra Jawa telah melalui kurun waktu yang panjang, yakni setidak-tidaknya, kurun waktu berlakunya bahasa Jawa Kuna, penggunaan bahasa Jawa Pertengahan (Jawa Tengahan), hingga berlakunya bahasa Jawa baru sekarang ini. Oleh karena itu, periodisasi sastra Jawa, secara garis besar dimulai dari sastra Jawa Kuna dan Jawa Tengahan, yang banyak diwarnai oleh kebudayaan Hindu dan Budha; sastra Jawa jaman Islam yang juga diwarnai oleh kebudayaan Islam; dan sastra Jawa Modern yang diwarnai oleh kebudayaan modern. Tentu saja berbagai pengaruh ini masih dapat ditemukan jejaknya sehingga menjadi ciri khas yang melekat pada jenis-jenis sastra Jawa dan dengan berbagai bentuknya masing-masing. Oleh karena itu keilmuan sejarah sastra, khususnya sejarah sastra Jawa, sangat diharapkan menyumbangkan kontribusinya secara memadahi. Dalam hubungannya dengan karya sastra itu sendiri, karya sastra harus dipandang sebagai suatu struktur yang bermakna. Dalam hal ini, meskipun penekanannya pada struktur karya sastra yang cenderung otonom, namun seperti halnya pada pembicaraan teori-teori pada keilmuan lain, ciri-ciri khas yang melekat pada jenis karya sastra Jawa, perlu mendapatkan perhatian tersendiri 39 dalam rangka pembicaraan mengenai unsur-unsur sastra Jawa, baik unsur intrinsik maupun ekstrinsik karya sastra yang bersangkutan. Struktur sastra Jawa Kuna kakawin pada umumnya, tentu berbeda eksistensinya dengan struktur sastra Jawa Pertengahan kidung, dan juga berbeda lagi dengan struktur karya sastra Jawa modern geguritan; meskipun ketiganya itu dapat dikategorikan sebagai kelompok puisi. Struktur sastra Jawa Kuna dan Pertengahan yang berkonteks Hinduisme tentu berbeda dengan struktur sastra Jawa Baru Pesisiran yang berkonteks Islami, struktur sastra suluk yang banyak bernuansa Islam-kejawen dan tentu juga berbeda dengan struktur sastra pada jenis-jenis sastra Jawa modern yang telah mengadopsi pengaruh kebudayaan Barat. Dengan demikian kompleksitas keilmuan tentang struktur karya sastra Jawa juga harus dipahami dalam kerangka pemetaan secara menyeluruh, khususnya eksistensi masing-masing karya sastra itu sendiri dan dalam hubungannya dengan pemaknaan struktur yang lebih luas, yakni dalam hubungannya dengan kebudayaan Jawa. Dalam hubungannya dengan pengarang dan proses penciptaan karya sastra, berbagai pandangan hidup hingga tata cara kehidupan keseharian pengarang berpengaruh terhadap terciptanya karya sastra, baik disadari atau pun tidak. Pandangan hidup pengarang dianggap sebagai dasar yang menentukan makna karya sastra. Proses penciptaan karya sastra didasari oleh sejarah kehidupan serta visi dan misi pengarang. Hal seperti inilah yang sering memunculkan pandangan bahwa pemaknaan karya sastra dianggap salah karena tidak sesuai dengan apa yang menjadi maksud pengarang. Tentu saja hal seperti ini harus dikaji secara lebih jauh lagi, mengingat kehidupan yang dilalui oleh pengarang yang sering kali sangat dinamis, bahkan jauh berbeda dari waktu ke waktu. Kehidupan pengarang dengan segala pandangan hidupnya yang berlaku pada para kawi tentu sangat berbeda dengan pandangan hidup para pujangga pada masa Kerajaan Islam di Jawa, berbeda lagi dengan pandangan hidup para sastrawan Islami di Pesisiran, apalagi dengan pandangan hidup para pengarang dan sastrawan Jawa modern yang tercermin pada jenis novel Jawa modern, geguritan atau jenis-jenis sastra Jawa gagrag anyar lainnya. Bahkan sesama 40 pengarang sastra Jawa modern, juga harus diperhatikan latar belakang masingmasing. Pendekatan dari segi pengarang ini juga mendapat sandungan permasalahan dalam momen-momen kehidupan sastra Jawa. Dalam hal ini, antara lain dengan adanya sejumlah besar karya sastra Jawa yang belum atau tidak akan pernah diketahui lagi siapa pengarangnya, baik dalam sastra tulis, apa lagi dalam bentuk sastra lisan. Kendala dan sandungan lainnya, misalnya ditemukan dalam bentuk tradisi menulis karya sastra yang didasari oleh perintah raja atau pesanan dari pihak-pihak tertentu, yang boleh jadi bersifat menafikan pandangan hidup pengarang. Tekanan politik penguasa tertentu, mungkin akan menyamarkan atau bahkan menghilangkan semua ciri kebanggaan pengarangpengarang tertentu. Namun demikian juga tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan mengungkapkan pandangan hidup pengarang akan sangat menyumbangkan kontribusinya yang berupa berbagai pemikiran yang mendasari pemaknaan karya sastra khususnya, dan pada gilirannya akan menyumbangkan kontribusinya pada keilmuan teori sastra Jawa secara umum. Dalam hubungannya dengan sidang pembaca, makna karya sastra dianggap menjadi hak pembaca untuk menafsirkannya. Dalam hal ini pembaca dapat berdiri sebagai pribadi seorang pembaca, namun sekaligus latar belakang sosial budaya kehidupan pembaca dapat berpengaruh terhadap pemaknaan karya sastra. Dengan demikian berbagai pemaknaan karya sastra dapat dianggap sah dan benar adanya, meskipun dari waktu ke waktu pemaknaan itu cenderung berubah-ubah. Pada kenyataannya, berbagai nuansa pemaknaan yang berbeda-beda justru akan menambah kemungkinan-kemungkinan obyektifitas dan generalitas nilai-nilai yang terkandung pada suatu karya sastra. Pandangan-pandanga kritikus postmodernisme, poststrukturalisme, dekonstruksi dan sebagainya, telah mewarnai wacana-wacana pemaknaan karya sastra secara berbeda, namun sekaligus memperkaya kesadaran adanya nilai-nilai lain dalam suatu karya sastra. Dalam sastra Jawa tradisional, misalnya pada karya sastra fiksi-historis, seperti cerita Pembayun dan Mangir Wanabaya, cerita Minak 41 Jingga dan Kencana Wungu, cerita Rara Mendut dan Tumenggung Wiraguna, dsb. Pernah mendapatkan sorotan yang berbeda dari pemerhati-pemerhati yang dekonstruktif. Mangir Wanabaya yang secara tradisi sering disudutkan keberadaannya sekali waktu mendapat perhatian khusus tentang keberanian dengan kebenaranya. Minak Jingga yang secara tradisi disudutkan sebagai pihak pemberontak, sekali waktu muncul sebagai protagonis yang benar dan berani menagih janji dari Ratu Kencana Wungu. Tumenggung Wiraguna yang secara tradisi disudutkan sebagai tokoh yang bengis, dapat ditampilkan sebagai sosok yang kebapakan dan sekedar mempertahankan prestise dan prestasinya, dsb. Semuanya itu justru dapat menjadi acuan-acuan baru dalam membuka nuansanuansa makna karya sastra dari pendekatan pembaca. Namun demikian dalam hubungannya dengan teori sastra Jawa tentu saja hal itu haruslah dilalui dengan filter-filter obyektif dan mengeliminir pandanganpandangan subyektif demi mendapatkan teori yang lebih universal, sekaligus menorehkan catatan-catatan spesifik pada karya-karya sastra tertentu, yang pada gilirannya juga dapat menawarkan makna-makna manusiawi dari karya sastra. Teori sastra Jawa, setidak-tidaknya harus menyangkut keempat ranah teori tersebut di atas, sehingga dapat dikembangkan menuju konsep-konsep yang lebih dalam, lebih spesifik pada klasifikasi tertentu, mulai dari struktur bleger karya sastra hingga pada ranah filosofi sastra. Pada kenyataannya keluasan materi teori sastra Jawa itu menuntut pengalaman jiwa setiap pemerhati sastra Jawa sehingga mampu menjangkau setidaknya teori yang bersifat mendasar dan sekaligus menyeluruh. BAB III. KHASANAH SASTRA JAWA KUNA A. Berlakunya Bahasa Jawa Kuna dan Munculnya Sastra Jawa Kuna Yang dimaksudkan sastra Jawa Kuna adalah karya sastra Jawa yang menggunakan bahasa yang dikategorikan sebagai bahasa Jawa Kuna dan bahasa Jawa Pertengahan. Secara administratif, peninggalan dari jaman Jawa Kuna yang menggunakan bahasa Jawa Kuna, yang ditemukan paling tua adalah prasasti Sukabumi yang menurut penanggalannya bertepatan dengan tanggal 25 maret 42 tahun 804. Meskipun berupa bukti ex silentio, yakni bukti bisu tanpa penjelasan lain, namun tanggal inilah yang oleh Zoetmulder (1983: 3) dianggap sebagai tonggak yang mengawali sejarah bahasa Jawa Kuna. Dalam hal karya sastranya, di antara bahasa-bahasa Nusantara, bahasa Jawa memiliki kedudukan yang istimewa, karena memiliki peninggalan yang tertua di antaranya. Bila bahasa Melayu, Aceh, Batak, Minangkabau, Sunda, Bugis dan Bali, memiliki peninggalan karya sastra tertua dengan angka tahun sekitar tahun 1600-an, sastra dalam bahasa Jawa Kuna sebagian berasal dari abad ke-9 dan ke-10. Ciri yang menonjol dalam bahasa Jawa Kuna adalah banyaknya kosa kata yang berasal dari bahasa Sansekerta. Menurut perkiraan Gonda, puisi Jawa Kuna yang disusun dalam metrum-metrum India (kakawin) mengandung kurang lebih 25 persen sampai 30 persen kesatuan kata yang berasal dari bahasa Sansekerta. Namun demikian, secara umum bahasa Jawa Kuna tetap mempertahankan struktur yang berciri bahasa Nusantara (Zoetmulder, 1983: 89). Seperti diketahui bahwa struktur bahasa Sansekerta itu bersifat fleksi, yakni dalam hubungannya dengan waktu kejadiannya dan pelakunya mengalami perubahan-perubahan kata kerja dan kata benda, seperti halnya dalam bahasabahasa Indo-Eropa (Jerman, Inggris, dsb). Sedang bahasa-bahasa Nusantara bersifat aglutinasi, yakni sekedar merangkai kata dengan mengurutkan saja. Akhir masa berlakunya bahasa Jawa Kuna (dan Jawa Pertengahan), dalam bentuk percakapan, ditandai oleh runtuhnya Majapahit dan mulai masuknya pengaruh Islam. Pada tahun 1512, kerajaan Daha mengirimkan perutusan ke pihak portugis. Kerajaan ini masih merupakan kerajaan HinduJawa, namun beberapa saat kemudian kerajan ini lenyap. Tinggallah kerajaan kecil diujung pulau Jawa yakni di Blambangan yang masih merupakan kerajaan Hindu Jawa. Pada akhir abad ke-17 kerajaan itu pun musnah dan digantikan oleh penguasa-penguasa Islam. Ini menandakan tamatnya sastra Jawa Kuna yang selama enam abad mewujudkan kebudayaan Hindu Jawa. Sejak runtuhnya Majapahit dan peralihan agama Hindu ke agama Islam terdapat ceritera-ceritera legendaris betapa berbagai buku-buku peninggalan Hindu Jawa dimusnahkan dan dibakar. Namun demikian masih ada beberapa buku yang tertinggal hingga saat ini, seperti cerita wayang Mahabharata dan 43 Ramayana yang masih juga bertahan hingga kini. Dari sisi sastra tertulis memang hanya sedikit hasil karya sastra Hindu Jawa yang tersisa, antara lain syair Jawa Kuna Ramayana dan Arjunawiwaha. Bersyukurlah di Bali, kraton-kraton dan kasta Brahmin menjadi pelindung setia bagi warisan sastra Jawa Kuna (Zoetmulder, 1983: 25). B. Hasil-hasil Karya Sastra Jawa Kuna dan Jawa Pertengahan Poerbatjaraka dalam bukunya Kapustakan Djawi (1952 atau 1964) membagi khasanah sastra Jawa Kuna setidak-tidaknya menjadi lima bagian, yakni (1) kitab-kitab yang tergolong tua dan berbentuk prosa, (2) kitab-kitab yang menggunakan puisi kakawin, (3) kitab-kitab yang termasuk muda, (4) kitab-kitab yang menggunakan bahasa Jawa Tengahan berbentuk prosa, dan (5) kitab-kitab yang berbentuk kidung (Puisi Jawa Pertengahan). Dalam buku Kapustakan Djawi tersebut karya-karya sastra Jawa Kuna yang berbentuk prosa golongan tua yakni: Serat Candakarana, Serat Ramayana, Sang Hyang Kamahayanikan, Brahmandapurana, Agastyaparwa, Uttarakanda, Adiparwa, Sabhaparwa, Wirataparwa, Asramawasanaparwa (dalam buku berjudul Asramawasaparwa), Udyogaparwa, Bhismaparwa, Kalangwan karya Zoetmulder dituliskan Mosalaparwa, Prasthanikaparwa, Swargarohanaparwa, dan Kunjarakarna. Sedang karya-karya yang berbentuk kakawin yakni: Arjunawiwaha, Kresnayana, Sumanasantaka, Smaradahana, Bhomakawya (Bhomantaka), Bharatayudha, Hariwangsa, Gatotkacasraya, Wrettasancaya (Cakrawaka-duta), dan Lubdhaka (Siwaratrikalpa). Kitab-kitab parwa adalah kitab-kitab berbentuk prosa Jawa Kuna yang merupakan bagian-bagian dari epos panjang Mahabharata. Kitab-kitab parwa, dalam Kapustakan Djawi di atas dimasukkan golongan tua. Dalam Kalangwan, pada bagian sastra parwa juga dibahas kitab Uttarakanda yang oleh Zoetmulder (1983: 97) dipandang mirip dengan kitab-kitab parwa, baik dalam caranya bahan dibahas, dalam bahasa maupun gayanya. Zoetmulder menyebut bahwa dari bagian mukadimahnya Uttarakanda mungkin ditulis pada abad ke-10. Dengan demikian mungkin yang terakhir ini dapat juga diklasifikasikan sebagai kitab Jawa Kuna golongan tua. 44 Adapun karya-karya yang digolongkan karya Jawa Kuna muda adalah bentuk-bentuk kakawin yang mencakup: Brahmandapurana, Kunjarakarna, Nagarakretagama, Arjunawijaya, Sutasoma atau Purusadasanta, Parthayadnya, Nitisastra, Nirathaprakerta, Dharmasunya, dan Harisraya. Zoetmulder ( 1983: 480-507) juga membicarakan kakawin-kakawin yang disebutnya sebagai kakawin minor, yakni kakawin-kakawin yang muncul belakangan, waktu penulisannya sekitar akhir kerajaan Majapahit hingga abad ke-19, yang mutunya relatif kurang atau rendah. Kakawin yang dimaksud antara lain Subhadrawiwaha, Abhimanyuwiwaha, Hariwijaya, kisah-kisah tentang Krsna, dan Narakawijaya. Hasil-hasil karya sastra jenis prosa yang menggunakan bahasa Jawa Tengahan adalah : Tantu Panggelaran, Calon Arang, Tantri Kamandaka, Korawasrama, dan Serat Pararaton. Sedang yang berbentuk kidung (puisi Jawa Pertengahan), adalah: Dewa Ruci, Serat Sudamala, Serat kidung Subrata, Serat Panji Angreni, dan Serat Sri Tanjung. Di samping itu, dalam Kalangwan masih tercatat Kidung Harsawijaya, Ranggalawe, Sorandaka, Kidung Sunda, dan Waseng (Sari). Dari segi substansinya, karya-karya berbahasa Jawa Kuna pada umumnya banyak berisi cerita-cerita kepahlawanan yang berasal dari India, terutama yang bersumber dari Mahabharata dan Ramayana. Sedangkan karya-karya berbahasa Jawa Pertengahan, sebagiannya telah berlatar situasi dan kondisi di Jawa, atau bahkan sebagiannya berhubungan dengan realita sejarah di Jawa ketika itu. C. Cara Penentuan Umur Karya Sastra Jawa Kuna Dalam karya sastra Jawa Kuna, tidak pada setiap karya, di dalamnya dituliskan siapa pengarangnya dan kapan dituliskannya. Oleh karena itu untuk menentukan umur karya sastra harus dengan cara-cara tertentu. Poerbatjaraka (1964: 38) dalam membicarakan karya-karya yang termasuk karya Jawa Kuna golongan muda, umurnya ditentukan dengan ciri-ciri yang ditetapkan dari : (1) nama raja pelindung dan dalam hubungannya dengan tulisan-tulisan lainnya, seperti tulisan pada batu tertentu, 45 (2) masa tertentu atau angka tahun tertentu, (3) ciri kebahasaan tertentu, (4) karya Jawa Kuna yang menjadi babon atau sumbernya, bila ada, (5) menceritakan keadaan di Tanah Jawa. (6) Untuk kriteria nomor 4 dan 5 di atas, tidak ada pada karya sastra yang digolongkan sebagai karya Jawa Kuna tua. Khusus dalam Wirataparwa, Zoetmulder (1983: 110) mengutip bagian akhir dari Wirataparwa, yang berisi hal yang tidak ditemukan dalam kitab parwa yang lain, yakni kejelasan cara menuliskan penanggalan. Penanggalan itu terdapat dalam dialog antara tokoh Waisampayana dengan raja Janamejaya, yang terjemahannya sebagai berikut. “….Kita mulai membaca cerita ini pada hari ke15 bulan gelap, dalam bulan Asuji, harinya Tungle, Kaliwon, Rabu pada wuku Pahang, dalam tahun 918 penanggalan Saka. Dan sekarang ialah Mawulu, Wage, Kamis dalam wuku Madangkungan, pada hari ke-14 paro petang dalam bulan Karttika. Jadi waktunya genap satu bulan kurang satu hari. Pada hari kelima Baginda tidak menitahkan diadakannya suatu pertemuan, karena Baginda terhalang oleh urusan lain. Menterjemahkan cerita ini ke dalam bahasa Jawa Kuna minta waktu cukup banyak. Duli mengharapkan, agar pembawaan tidak melampaui kesabaran Baginda dan tidak dianggap terlalu panjang.”. Menurut catatan Zoetmulder, tanggal tersebut di atas bertepatan dengan tanggal 14 Oktober sampai 12 Nopember tahun 996. Adapun dalam Adiparwa, Bhismaparwa, dan Uttarakanda, pada mukadimahnya dilengkapi dengan menyebut raja pelindung, yakni Sri Dharmawangsa Teguh Anantawikramottunggadewa. Dengan demikian kitabkitab parwa tersebut mungkin ditulis pada akhir abad ke-10 (Zoetmulder, 1983: 111), yakni pada masa hidupnya raja Sri Dharmawangsa Teguh. D. Metrum Sastra Kakawin dan Kidung Istilah kakawin berasal dari metrum-metrum di India, sedang istilah kidung bersifat Jawa asli. Kata kawi berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti ‘seorang yang mempunyai pengertian yang luar biasa, seorang yang bisa melihat hari depan, seorang bijak’. Dalam tradisi Jawa Kuna istilah kawi lalu berarti 46 ‘seorang penyair’. Sufiks ka- -n pada kakawin berasal dari bahasa Jawa asli, sehingga kakawin merupakan istilah belasteran, yang berarti ‘karya seorang penyair, syairnya’. Dengan demikian istilah kakawin dalam bahasa Jawa Kuna padanannya dalam bahasa Sansekerta adalah istilah kawya (Zoetmulder, 1983: 119-120). Pada umumnya, atau perkecualiannya hanya sedikit, kaidah-kaidah metris yang berlaku pada kakawin sama dengan kaidah-kaidah yang berlaku bagi persajakan kawya dalam bahasa Sansekerta. Kaidah itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Metrum kakawin disebut wrtta, yakni variasi penempatan guru dan laghu. Adapun yang disebut guru adalah: 1. Suku kata terbuka bervokal panjang 2. Vokal rangkap, atau vokal e atau o 3. Suku kata terbuka bervokal pendek yang diikuti konsonan rangkap 4. Suku kata terteutup. Selain keempat poin tersebut disebut laghu. Adapun aturan atau metrum kakawin pada umumnya ditentukan sebagai berikut. 1. Sebuah bait terdiri atas empat baris, kecuali jenis kakawin yang disebut Wisama, yang hanya terdiri atas 3 baris saja. 2. Masing-masing baris meliputi jumlah suku kata yang sama, disusun menurut pola metris yang sama. Jumlah suku kata setiap baris kakawin disebut chanda. 3. Kuantitas setiap suku kata, panjang atau pendeknya, atau guru dan laghunya ditentukan oleh tempatnya dalam baris serta syaratsyaratnya. 4. Suku kata dianggap pendek (laghu) bila merupakan suku kata terbuka dengan diakhiri oleh bunyi vokal a, i, u, dan ê. 5. Suku kata dianggap panjang (guru) bila mengandung sebuah vokal panjang (ä, ï, ü, ö, e, o, dan ai) 6. Suku kata juga dianggap panjang (guru) bila sebuah vokal pendek disusul oleh lebih dari satu konsonan. 47 7. Suku kata terakhir dalam setiap baris dapat bersifat panjang atau pendek (anceps). 8. Aneka macam pola metrum kakawin Jawa Kuna memiliki namanya masing-masing. 9. Metrum-metrum kakawin tidak mengenal persajakan apapun. Sebagai contoh metrum Prthwïtala (dari Bhäratayuddha (10.12) sebagai berikut. Mulat mara sang Arjunäsêmu kamänusan kasrêpan ri tingkah i musuh nira n pada kadang taya wwang waneh hana pwa ng anak ing yayah mwang ibu len uwanggêh paman makädi nrpa Salya Bhïsma sira sang dwijanggêh guru Pola metrisnya dapat digambarkan sebagai berikut. . Tanda menandakan suku kata pendek (laghu), sedang tanda menandakan suku kata panjang (guru). Pada akhir baris, tanda berarti boleh pendek atau panjang. Tanda pada setiap tiga suku kata hanya dipakai agar jelas, dan pada metris India setiap tiga suku kata ditandai oleh satu huruf Devanagari tertentu. (Terjemahannya: ‘Ketika Arjuna melihat sekelilingnya ia nampak terharu sekali, iba dan sedih, karena semua musuh itu termasuk kaum kerabatnya, tak ada satu orang asing di antara mereka. Ada saudara sepupu, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, lagi pula paman-pamannya, terutama Salya, kemudian Bhisma (dan Drona), sang brahmin, yang pernah menjadi gurunya’) Biarpun satu bait saja dapat disebut kakawin, misalnya sajak cinta yang hanya satu bait saja, namun kebanyakan kakawin terdiri atas beberapa bait yang berturut-turut memakai metrum yang sama sehingga membentuk sebuah pupuh tertentu. Setiap pupuh dibedakan menurut variasi dalam metrumnya. Tidak ada ketentuan berapa jumlah bait dalam satu pupuh. Juga tidak ada ketentuan yang menghubungkan antara tema tertentu dengan sifat metrum tertentu (Zoetmulder, 1983: 121-122). Kaidah kakawin di atas, kadang terdapat kekecualian. Kadang-kadang baris-baris ganjil (1 dan 3) berbeda dengan baris genapnya (2 dan 4). Dalam hal 48 ini sering terjadi penambahan satu suku kata pada baris genapnya. Seperti pada metrum Waitälïiya, sebagai berikut. Dalam metrum ini setelah suku kata ke tiga pada baris ke-2 dan ke-4, disisipkan tambahan satu suku panjang. Disamping itu kadang terdapat metrum Indrabajra dan Upendrabajra, dengan jumlah suku kata yang sama tetapi pola metrumnya berbeda, terpadu dalam kuartren yang sama. Misalnya dalam Sumanasantaka, Canto (pupuh) 170. Metrumnya sebagai berikut. Ada lagi metrum Wisama yang memiliki kategori tersendiri, yakni terdiri atas tiga baris per bait, masing-masing dengan panjang yang berbeda. Misalnya dalam Udgatawisama, dengan pola sebagai berikut. Akhirnya yang juga spesifik adalah metrum Dandaka. Di sini hampir tidak lagi dapat dikatakan sebagai bait. Sesudah 6 suku kata pendek yang mengawali setiap baris, disusul serangkaian anapaes () atau amphimacer () dan pola ini diulang sampai empat kali: n () Besarnya angka n }4X berbeda-beda menurut tipe Dandaka yang bersangkutan, dan dapat mencapai angka 40 lebih. Di India, buku-buku pegangan mengenai prosodi atau ilmu persajakan seperti dalam kakawin, disebut chandahsastra. Mpu Tanakung dalam karyanya Wrttasancaya (Cakrawaka-duta) menyatakan bermaksud menulis berdasarkan 49 chandahsastra India. Yang dimaksud chanda ternyata bukan pola metris, tetapi hanya jumlah suku kata tiap baris, sebagai berikut. ukta adalah 1 suku kata dalam satu baris atyukta 2 suku kata dalam satu baris madhyama 3 suku kata dalam satu baris pratistha 4 suku kata dalam satu baris supratistha 5 suku kata dalam satu baris gayatri 6 suku kata dalam satu baris usnih 7 suku kata dalam satu baris anustubh 8 suku kata dalam satu baris brhati 9 suku kata dalam satu baris pangkti 10 suku kata dalam satu baris, dan seterusnya, secara urut sebagai berikut. 11 suku kata adalah tristapa, lalu jagati, lalu atijagati, sakwari, atisakwari, asti, atyasti, dhrti, atidhrti, krti, prakrti, akrti, wikrti, sangskrti, abhikrti, dan 26 suku kata adalah wyukrti. Lalu Tanakung juga membahas wrtta, yakni mengenai tempat dan penyusunan suku kata panjang dan yang pendek (guru-laghu). Istilah wrtta menunjukkan metrum yang ditentukan oleh pembagian kuantitas dalam setiap baris. Chanda yang sama dapat meliputi bermacam-macam wrtta yang berbedabeda. Misalnya sama-sama gayatri (6 suku kata tiap baris) namun pola aturan panjang pendeknya bisa berbeda-beda. Untuk menjelaskan hal di atas, Tanakung menyusun cerita dalam bentuk kakawin berjudul Wrttasancaya, yang terdiri atas sejumlah bait dan tiap baitnya menggunakan metrum yang berbeda. Nama metrumnya dituliskan pada baris terakhir. Contohnya metrum Bhramarawilambita, sebagai berikut. yasa malango hineduk racana nikang talaga kusuma katangga sunar bhramarawilambita ya Metrum tersebut 8 suku kata disebut Anustubh, polanya . Dari baris terakhir dapat diketahui bahwa nama metrumnya adalah Brahmarawilambita (lebah bergantung). 50 Zoetmulder (1983: 131), mencatat bahwa terdapat perbedaan besar antara praktik dalam puisi Jawa Kuna dengan praktik dalam puisi di India, terutama dalam penggunaan nama-nama metrum favorit. Ada beberapa nama metrum Jawa Kuna yang tidak terdapat di India. Perbedaan yang paling menyolok, ialah jumlah metrum yang paling populer dalam tradisi Jawa Kuna, tidak terdapat dalam tradisi kepenyairan India. Dalam tradisi kepenyairan Jawa Kuna terdapat metrum utama, yakni metrum Jagaddhita (23 suku kata) yang terdapat dalam setiap kakawin. Metrum yang menduduki popularitas kedua ialah Sardulawikridita (19 suku kata). Berbeda dengan puisi Jawa Kuna yang disebut kakawin, puisi Jawa Pertengahan yang disebut kidung tidak menggunakan metrum dari India, tetapi bermetrum asli Jawa, yakni menggunakan metrum yang biasa disebut sebagai metrum tengahan, dengan patokan sebagai berikut (Zoetmulder, 1983: 142). (1) Jumlah baris pada setiap bait tetap sama selama metrumnya tidak berganti. Semua metrum tengahan mempunyai lebih dari empat baris (berbeda dengan kakawin). (2) Jumlah suku kata pada baris tertentu tetap, tetapi panjang tiap baris berbeda-beda menurut kedudukan baris itu pada tiap bait. (3) Sifat sebuah vokal setiap suku kata terakhir pada tiap baris juga tertentu menurut baris tertentu dalam suatu bait. Metrum tembang tengahan tersebut mempunyai prinsip seperti dalam tembang macapat, seperti yang dinyatakan Padmosoekatjo (tt, jilid I: 23-24), sebagai berikut. Tembang tengahan dan tembang macapat penyusunannya berdasarkan guru gatra, guru wilangan dan guru lagu. Artinya, dalam tembang tengahan dan macapat, setiap bait sudah tertentu jumlah barisnya (guru gatra atau cacahing gatra), jumlah suku katanya (guru wilangan atau cacahing wanda), dan jatuhnya vokal pada akhir baris (dhong-dhing atau guru lagu). Guru gatra ialah jumlah baris setiap bait. Guru wilangan ialah jumlah suku kata setiap baris. Sedang guru lagu ialah bunyi vokal pada suku kata di akhir baris. Menurut Zoetmulder, perbedaan kidung (tembang tengahan) dengan tembang macapat, terutama adalah dalam perangkaian bait menjadi pupuh. Dalam kidung kadang-kadang satu pupuh dipadu dengan pupuh yang lain hanya 51 dalam sedikit bait. Zoetmulder (1983: 143) mencontohkan sebagai berikut. Sebuah pupuh dapat disusun dengan sebuah kata pengantar terdiri atas dua bait dengan metrum A dan dua bait dengan metrum B, kemudian batang tubuhnya silih berganti dua bait metrum C dan dua bait metrum D. Kadang juga disusul dua bait metrum E. dan seterusnya. Padmosoekatjo (tt, jilid I: 22) secara lebih jelas membagi antara metrummetrum tembang tengahan dengan metrum-metrum tembang macapat. Yang termasuk tembang tengahan ada 5 (lima) macam, yakni: Megatruh (dudukwuluh), Gambuh, Balabak, Wirangrong, dan Jurudemung. Sedang yang termasuk tembang macapat ada 9 (sembilan) macam, yakni Kinanthi, Pucung, Asmaradana, Mijil, Maskumambang, Pangkur, Sinom, Dhandhanggula dan Durma. Sedang Poerbatjaraka dalam bukunya Kapustakan Djawi (1952: 69 dan 71), dalam rangka menjelaskan tentang tembang tengahan, memberikan dua buah catatan kaki yang menyatakan bahwa tembang tengahan itu sebenarnya tidak ada, yang ada adalah tembang macapat. Yang disebut tembang tengahan itu sebenarnya tembang macapat yang tergolong tua yang hampir dilupakan orang. Dalam pada itu terdapat sejumlah metrum yang sedikit berbeda antara tembang tengahan dengan tembang macapat pada nama tembang yang sama. Poerbatjaraka memberikan catatan untuk membedakan teks Jawa Tengahan dengan Jawa Baru dengan menyebut bahwa tembang Sinom berbahasa Jawa Tengahan, baris ketiganya berakhir dengan guru lagu bervokal o bukan a, seperti pada tembang Sinom bahasa Jawa Baru (1952: 105). Tembang Pamijil Jawa Pertengahan pada baris kedua berakhir dengan guru lagu bervokal e sedang dalam tembang Mijil bahasa Jawa Baru bervokal o (1952: 78). E. Sarana Penulisan Sastra Jawa Kuna Ada beberapa sarana yang biasa dipergunakan sebagai alat untuk menuliskan karya sastra Jawa Kuna, antara lain: 1. Daun lontar (rontal) dan pengutik. Daun lontar banyak dipergunakan sebagai alat tulis sastra Jawa Kuna. Hingga saat ini, terutama di Bali, 52 daun lontar masih dipergunakan sebagai alat yang ditulisi. Pengutik atau pengrupak, adalah sebuah pisau besi kecil yang hingga sekarang di bali mesih dipergunakan sebagai alat untuk menulis. 2. Tanah dan karas. Tanah adalah alat yang dipakai untuk menulis. Tanah adalah semacam pensil yang dapat dipertajam dengan kuku, dan dibuang setelah patah atau mengecil menjadi puntung. Sedang karas ialah bahan atau papan yang ditulisi dengan tanah. 3. Pudak atau ketaka atau ketaki dan cindaga. Pudak adalah bunga pohon pandan. Yang ditulisi adalah daun bunga pudak yang berwarna putih dan bila tergores lalu membekas hitam. Setiap benda yang tajam dapat dipakai sebagai penulisnya. 4. Yasa, bale, mahanten, rangkang, mananten atau patani adalah sebuah bangunan atau pondok tempat ditemukannya kakawin-kakawin. Jadi di bangunan itu ditemukan tulisan-tulisan. 5. Teto atau wilah adalah bagian dari bangunan yasa dsb. yang merupakan bagian yang ditulisi atau dihiasi dengan lukisan-lukisan tertentu. BAB IV. KHASANAH SASTRA JAWA MODERN Secara umum dapat dikatakan bahwa sastra Jawa Modern ialah karya sastra yang menggunakan media bahasa Jawa Baru (dalam istilah lain sering disebut juga bahasa Jawa Modern). Pada umumnya karya sastra ini juga dihasilkan oleh masyarakat yang berbahasa Jawa Baru yang pada saat ini, secara geografis politis termasuk dalam propinsi Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta dan Jawa Timur. Meskipun di antara daerah-daerah tersebut berlaku bahasa Jawa Baru yang bersifat dialektis, namun secara umum ciri pengenalnya tidak jauh berbeda. Penggunaan bahasa Jawa Baru pada umumnya dapat dibatasi pada 53 waktu setelah masuknya pengaruh Islam di Jawa, sehingga sebagian ciri-ciri lunguistiknya diwarnai oleh pengaruh bahasa Arab dan budaya Islam. Poerbatjaraka dalam Kapustakan Djawi (1952) menyatakan bahwa ketika Majapahit berada di puncak kejayaan, sedikit orang Islam telah masuk di Jawa. Ketika Majapahit mulai rapuh karena banyak terjadi pemberontakan, Islam di Jawa mulai maju. Dan di atas telah disinggung bahwa menurut Zoetmulder (1983: 25) akhir masa berlakunya bahasa Jawa Kuna (dan Jawa Pertengahan), dalam bentuk percakapan, ditandai oleh runtuhnya Majapahit dan mulai masuknya pengaruh Islam. Pada tahun 1512, kerajaan Daha mengirimkan perutusan ke pihak portugis. Kerajaan ini masih merupakan kerajaan HinduJawa, namun beberapa saat kemudian kerajan ini lenyap. Tinggallah kerajaan kecil diujung pulau Jawa yakni di Blambangan yang masih merupakan kerajaan Hindu Jawa. Pada akhir abad ke-17 kerajaan itu pun musnah dan digantikan oleh penguasa-penguasa Islam. Ini menandakan tamatnya sastra Jawa Kuna yang selama enam abad mewujudkan kebudayaan Hindu Jawa. Dengan demikian secara praktis bahasa Jawa Baru mulai berlaku. Poerbatjaraka membicarakan sastra Jawa pada jaman Islam mulai dari Het Boek van Bonang. Namun demikian juga dinyatakan bahwa Het Boek van Bonang tersebut masih menggunakan bahasa Jawa Pertengahan. Dengan demikian tidak semua karya sastra Jawa yang mendapat pengaruh Islam merupakan karya sastra Jawa Modern. Namun ada kemungkinan yang menggunakan bahasa Jawa Pertengahan relatif Jaman Islam awal. Mungkin juga di daerah-daerah tertentu ketika itu, Bahasa Jawa Baru telah berlaku menjadi bahasa sehari-hari, namun belum lazim dipergunakan untuk bahasa sastra. A. Jenis-jenis Sastra Jawa Modern Berdasarkan Temanya Bila ditinjau dari segi isi pembicaraan atau tema-temanya, karya sastra Jawa Modern, dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yakni antara lain babad, niti, wirid, wayang menak, panji, novel dan cerkak, jagading lelembut, dongeng, biografi, kisah perjalanan, primbon dsb. yang bisa dijelaskan sebagai berikut. 1. Babad. 54 Kata babad semula berarti ‘menebas dengan pisau besar’. Dalam hubungannya dengan jenis sastra babad, agaknya kata babad dipergunakan secara lebih sempit, yakni ’menebangi pepohonan di hutan atau membuka hutan untuk dijadikan daerah pemukiman’. Kata ini mengingatkan pada lakon dalam cerita wayang purwa, yakni Babad Alas Wanamarta, yang bermakna membuka hutan Wanamarta untuk dijadikan kerajaan Indraprasta. Sastra babad pada umumnya berisi tentang sejarah lokal yang ditulis dengan cara pandang tradisional, sehingga dibumbui dengan berbagai cerita yang bersifat pralogis atau bahkan bersifat fiktif dan simbolik. Di dalamnya sering kali berisi genealogi, mitologi, legenda, cerita orang suci, kesaktian dan kekebalan tubuh terhadap senjata tajam, ramalan, mimpi, wahyu, dsb. yang dari segi logika sering kali tidak masuk akal. Babad sering ditulis dalam bentuk puisi (tembang), namun membentangkan bentuk kisahan atau naratif. Judul-judul sastra babad biasanya berhubungan dengan nama tempat, daerah, kerajaan, nama suatu kejadian atau peristiwa yang monumental, dsb. atau berhubungan dengan tokoh besar terentu. Yang berhubungan dengan nama tempat yakni antara lain: Babad pajajaran, Babad Majapahit, Babad Mataram, Babad Tanah Jawi, Babad Pakepung, Babad Clereng, Babad Lowano, dan Babad Giyanti. Yang berhubungan dengan suatu kejadian, antara lain: Babad Perang Sepei, Babad Bedhah Ngayogyakarta, Babad Palihan Nagari, dan Babad Pacina. Yang berhubungan dengan nama tokoh antara lain Babad Dipanegara, Babad Mangir, Babad Ajisaka, Babad Surapati, Babad Trunajaya, dsb. Penulisan babad pada umumnya berada di lingkungan kraton dengan rajanya selaku penguasa daerah yang bersangkutan, atau di lingkungan bangsawan yang lebih kecil, misalnya di kabupaten atau di kadipaten. Materi babad ditulis sebagian dengan menggunakan kisah nyata dan sebagiannya dengan menggunakan karya sastra fiktif atau cerita yang sudah ada, ditambah dengan pengalaman yang dihayati pribadi penulis dan para informan di sekitarnya. Pada umumnya babad ditulis dengan tujuan : (a) mencatat segala peristiwa, kejadian atau pengalaman yang pernah terjadi pada masa lampau, 55 memberikan gambaran kepada anak cucu untuk menunjukkan contoh dan sejarah sebagai cermin kehidupan; (b) untuk menjadi teladan yang baik untuk diambil manfaatnya; (c) untuk memperkuat sakti raja dan mengukuhkan legitimasinya; sebagai catatan sejarah bagi kepentingan penguasa dan keturunannya (Sedyawati, ed. 2001: 267). Babad juga bisa ditulis dalam rangka sanggahan terhadap cerita babad yang lainnya yang sekaligus berfungsi sebagai pembenaran pada kelompok tertentu. Dengan demikian, sering kali babad dutulis dalam versi-versi. Kejadian yang sama sering kali ditulis oleh beberapa penulis yang berbeda, dengan tujuan subyektif yang boleh jadi berbeda pula. Tidak berlebihan bila setiap penulis loyal terhadap tuannya masing-masing, maka tujuan penulisan babadnya sama-sama untuk mengukuhkan legitimasi penguasa masing-masing. Dengan demikian terjadi versi-versi penulisan babad. Misalnya saja, motif perseteruan antara Kademangan mangir (di Mangiran-Bantul) dengan Panembahan Senapati di Mataram, akan diceritakan secara berbeda antara penulis dari Mataram dengan penulis dari Mangiran. Babad Dipanegara yang ditulis atas penguasa yang pro Belanda, akan berbeda dengan yang ditulis atas penguasa yang pro Pangeran Dipanegara. Oleh karena itu dalam rangka pandangan babad sebagai karya historis, dalam studi komparatif harus dicermati lebih hati-hati, agar motif-motif dan kejadian-kejadian tertentu dapat dipertanggungjawabkan obyektifitasnya. 2. Niti atau Wulang atau Pitutur. Kata niti berasal dari bahasa Sansekerta yakni akar kata ni yang berati ‘menuntun’. Niti berarti ‘tuntunan’. Jenis sastra niti berisi tentang ajaran atau wulang atau pitutur ke arah kebaikan, antara lain tentang etika atau moral, tatacara atau upacara tradisi tertentu, sikap dan sifat-sifat seseorang dalam menghadap atau mengabdi pada raja atau penguasa, orang tua, dsb. Jenis sastra pitutur ini sebenarnya telah ada sejak periode sastra Jawa Kuna. Sastra niti dalam sastra Jawa modern, sebagian kecil muncul pada sekitar jaman Mataram awal, sebagai bangunan kembali sastra niti berbahasa Jawa Kuna. Sebagian lainnya digubah setelahnya, bersamaan dengan masa renaisance sastra Jawa, yakni suatu masa ketika banyak karya sastra Jawa Kuna disadur atau diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa Baru. Masa renaisance terjadi beberapa 56 waktu setelah kerajaan Mataram terpecah menjadi dua (tahun 1700-an AJ), yakni Kasunanan di Surakarta dan Kasultanan di Yogyakarta, yang ditandai dengan Perjanjian Giyanti. Sebagian sastra niti yang lain lagi muncul sebagai karya baru. Sebagai contoh Serat Panitisastra bersumber dari kitab Jawa Kuna yang berbentuk prosa atau dikenal dengan bentuk kawi-jarwa, berasal dari jaman Majapahit. Pada jaman Pakubuwana V, kitab ini disalin ke dalam bentuk tembang Dhandhanggula (satu metrum, yakni versi Pakubuwana V). Kemudian juga muncul versi lain (versi Sastranegara) yang ditulis dalam 10 metrum tembang macapat, dan versi 2 metrum macapat (versi Sastrawiguna). Di samping itu juga ditemukan dalam bentuk sekar ageng. Pada umumnya judul niti mempergunakan kata niti, wulang, sasana, atau sana. Banyak sastra niti ditulis dalam bentuk puisi tembang. Judul-judul sastra niti antara lain: Serat Niti Sruti (berangka tahun 1534 AJ), Serat Niti Praja (1641 AJ), Serat Sewaka (1699 AJ), Serat Wulang Reh (bersengkalan tata guna swareng nata atau 1735 AJ), Serat Nitisastra atau Panitisastra (bersengkalan nem catur gora ratu atau 1746 AJ), Serat Sanasunu (bersengkalan sapta catur swareng janmi atau tahun 1747 AJ), Serat Warayagnya (1784 AJ), Serat Wirawiyata (1789 AJ), Serat Sriyatna (1790 AJ), Serat Nayakawara (1791 AJ), Serat Candrarini (1792 AJ), Serat Paliatma (1799 AJ), Serat Salokatama (1799 AJ), Serat Pancaniti , dsb. Di samping itu di Jawa juga ditemukan serat-serat tuntunan yang bersifat Islami, yakni Serat Bustam, Serat Tajussalatin, dan Serat Nawawi. Dalam bentuk yang agak berbeda, sastra pitutur ini muncul berisi larangan-larangan tertentu, yakni dengan judul pepali, khususnya Serat pepali Ki Ageng Sela, dan berbentuk rangkuman prosesi budaya Jawa, khususnya Serat Tatacara. 3. Suluk dan Wirid Istilah suluk dalam khasanah sastra Jawa ada dua macam, yakni suluk pedalangan dan suluk yang berisi ajaran tasawuf. Suluk pedalangan ialah jenis puisi tembang, yang sering dilantunkan oleh seorang dalang dalam seni pewayangan, baik wayang kulit purwa atau jenis pertunjukan wayang lainnya. Suluk jenis ini berfungsi sebagai pendukung latar suasana pada bagian-bagian 57 cerita tertentu, misalnya untuk suasana sedih akan dilantunkan jenis suluk yang disebut tlutur. Pada umumnya, suluk pedalangan ini diambilkan dari jenis tembang gedhe yang merupakan pengaruh dari kakawin atau dari bentuk seloka dari sastera Sansekerta. Tidak berlebihan bila teks (cakepan) suluk pedalangan ini sering kali telah bergeser dari sumbernya, bahkan sebagian lagi sulit untuk diterjemahkan atau bahkan tidak dapat dilacak lagi dari mana sumber awalnya.. Dalam pedalangan di Jawa, isi teks (cakepan) suluk pedalangan tidak harus sesuai dengan cerita pokoknya, karena semata-mata hanya menekankan kesamaan suasana ceritanya. Berbeda dengan suluk pedalangan di Bali, yang isi teksnya banyak diambil dari bagian seloka-seloka Sansekerta atau kakawin Jawa Kuna yang sama dengan bagian cerita pedalangan yang dilakonkan oleh dalang yang bersangkutan. Adapun jenis sastra suluk yang berisi ajaran tasawuf, kata suluk di sini berasal dari kata salaka atau sulukun (bahasa Arab) yang berarti ‘pengembaraan’ atau ‘perjalanan’. Kata ini kemudian dihubungkan dengan makna hidup manusia, yakni perjalanan hidup yang harus ditempuh, atau pengembaraan hidup untuk mencari kebenaran Ilahi. Dari pandangan lain, sering juga terdengar penelusuran dari etimologi tradisional Jawa, yakni yang sering disebut kerata basa atau jarwadhosok. Keratabasa atau Jarwadhosok adalah memaknai kata dengan cara mencari kemungkinan kepanjangan kata tersebut. Dalam hubungannya dengan kata suluk, dinyatakan bahwa kata suluk berasal dari kata yen sinusul muluk yang berarti ‘kalau dikejar semakin membubung tinggi’. Maksudnya, keilmuan dalam suluk, bila semakin dipikirkan akan semakin jauh untuk dijangkau pikiran atau logika awam. Hal ini dikarenakan, permasalahan dalam suluk ini berhubungan erat dengan hal-hal gaib yakni hal supranatural dalam hubungannya dengan Tuhan dan kehidupan manusia. Oleh karena itu wajar bila sebagian besar karya suluk memiliki struktur yang tidak mudah dipahami maknanya atau relatif membingungkan, terutama bagi yang tidak biasa menggelutinya. Jenis sastra suluk ini berisi tentang ajaran kesempurnaan hidup dalam hubungannya dengan ajaran tasawuf Islam atau Islam-kejawen. Dalam ajaran ini 58 pada umumnya dibicarakan tentang sangkan paraning dumadi yakni asal dan tujuan hidup manusia. Di dalamnya, sering kali dijumpai idiom-idiom yang berhubungan dengan falsafah hidup dan masalah kemanusiaan dalam hubungannya dengan ketuhanan, atau bentuk isbat seperti nggoleki susuhing angin, nggoleki galihing kangkung, atau nggoleki tapaking kuntul nglayang (mencari sarang angin, mencari hati atau batang keras pada pohon kangkung, mencari jejak burung kuntul yang melayang) dan sebagainya. Sebagian sastra suluk ditulis dalam bentuk dialog, baik antara guru dengan murid, antara sahabat, antara orang tua dengan anak atau cucu, atau antara suami dengan isteri. Di Jawa, ajaran suluk ini dapat dibedakan menjadi suluk Islam dan Islamkejawen. Suluk Islam pada umumnya merupakan suluk yang berasal dari daerah Pesisiran (pantai) yang kental dengan pengaruh Islam. Suluk Pesisiran ini merupakan hasil gubahan dari masyarakat pesantren di pantai utara Jawa, sehingga cenderung menekankan ajaran transendensi Tuhan. Untuk menuju kesempurnaan hidup manusia harus menjalankan syariat Islam sehingga dapat dekat dengan Tuhan. Kemanunggalan manusia sebagai hamba dengan Tuhan tetap ada batas-batasnya. Manusia tetap berada pada kemanusiaannya dan tidak pernah menyatu luluh dengan Tuhan. Tuhan tetap di atas segala-galanya dan tak terjangkau oleh akal pikir dan jiwa-raga manusia. Eksistensi Tuhan semacam ini dalam suluk sering disebut tan kena kinaya ngapa yang berarti ‘tidak dapat diandai-andaikan’, atau adoh tanpa wangenan celak tanpa sesenggolan yang berarti ‘jauhnya tak berbatas dan meskipun dekat sekali tetapi tak dapat bersentuhan’. Adapun suluk Islam-kejawen, pada umumnya berasal dari daerah pedalaman, terutama pengaruh kraton. Suluk ini merupakan hasil olahan yang menekankan panteisme dan monisme, atau mengajarkan immanensi Tuhan (Tuhan bisa hadir dalam diri manusia). Oleh karena itu, di dalamnya sering berisi idiom-idiom seperti manunggaling kawula-Gusti atau jumbuhing kawula-Gusti (bersatunya hamba dengan Tuhannya). Kemanunggalan ini pada suatu saat dapat benar-benar luluh atau jumbuh, sehingga dapat mengaburkan batas-batas antara manusia dengan Tuhannya. Kemanunggalan itu sering digambarkan seperti curiga manjing warangka, warangka manjing curiga (bilah keris yang berada di 59 dalam sarungnya dan sarung yang berada di dalam bilahnya) atau kodhok ngemuli lenge (katak menyelimuti liangnya), dengan makna bahwa Tuhan yang berada dalam diri manusia menguasai dan melindungi manusia yang bersangkutan. Pada jenis suluk ini, sebagiannya menafikan syariat Islam dengan mengajarkan bahwa manusia harus selalu ingat kepada Tuhan dan bersembahyang setiap saat seiring dengan aktivitas keluar dan masuknya nafas. Ajaran suluk semacam ini dianggap menyimpang oleh kelompok Wali Sanga, dan beberapa tokoh yang mengajarkannya dihukum mati. Suluk semacam ini antara lain terdapat dalam ajaran Seh Sitijenar (dalam berbagai suluk yang menceritakan tokoh Seh Sitijenar) dan ajaran Ki Amongraga (dalam Suluk Tambangraras atau Serat Centhini). Sastra suluk pada umumnya ditulis dalam bentuk tembang (macapat). Namun juga ada yang berbentuk prosa, yang biasanya disebut wirid. Pada umumnya judul sastra suluk dimulai dengan kata suluk, atau wirid untuk prosanya. Contoh jenis suluk antara lain: Suluk Wujil (1529 AJ), Suluk Sukarsa, Suluk Malang Sumirang, Suluk Residriya, Suluk Seh Malaya, Suluk Tekawardi, Suluk Purwadaksina, Suluk Gontor, Suluk Luwang, dan masih banyak lagi. Adapun judul-judul wirid antara lain: Wirid Hidayat Jati dan Wirid Maklumat Jati. 4. Wiracarita Khasanah sastra Jawa diwarnai dengan kitab-kitab dan cerita-cerita lisan yang berbentuk roman berisi wiracarita, yang sebagiannya diimpor dari luar negeri, antara lain dari India (wayang purwa), dari Persi (Menak), dari Cina (wayang potehi), dsb. a) Sastra Wayang Kata wayang pada mulanya merujuk pada jenis pertunjukannya, yakni pertunjukan bayang-bayang. Kata wayang memang berarti ‘bayang-bayang’. Kata wayang, pada mulanya disinyalir dalam hubungannya dengan prosesi sebagai pemujaan kepada Hyang, atau dewa penguasa alam semesta. Bila mengacu pada pengertian pertunjukan ini, sastra wayang setidak-tidaknya terdiri atas cerita 60 kepahlawanannya (wiracarita), suluk pedalangannya, tembang-tembang yang dilagukan oleh para pesindennya (vokalis putri) dan senggakan atau gerongan yang dilagukan oleh para wiraswaranya (vokalis pria). Dalam hal cerita kepahlawanannya, sebagian cerita wayang merupakan cerita yang berasal dari India, khususnya pada jenis wayang purwa, yakni cerita yang bersumber pada kisah Mahabharata dan Ramayana. Namun demikian pada berbagai bagian cerita telah dibumbui dan diubah oleh orang Jawa, sehingga banyak sekali perbedaan-perbedaan dari cerita aslinya di India. Sastra wayang dari kedua sumber ini sudah ada sejak dalam khasanah sastra Jawa Kuna. Drama wayang ini sering disebut dengan istilah wayang purwa. Pada dasarnya cerita dalam wayang purwa dapat dikelompokkan dalam cerita siklus Arjunasasrabahu (dari Serat Lokapala), Siklus Rama (dari Ramayana) dan siklus Pandawa (dari Mahabharata). Selain pada wayang purwa, sebagian cerita wayang bersumber pada cerita Menak, cerita Panji, cerita binatang, atau beberapa di antaranya berasal dari cerita yang lain, yakni cerita keagamaan, atau cerita perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ada beberapa jenis cerita wayang Jawa, antara lain: wayang purwa (bersumber cerita dari Mahabharata, Ramayana, Lokapala, dsb.), wayang madya (bersumber dari cerita Anglingdarma, dari Serat Pustakarajamadya), wayang gedhog menceritakan tokoh Panji, wayang klithik menceritakan tokoh Damarwulan, wayang menak bersumber dari Serat Menak, wayang potehi (ceritera bersumber dari kepahlawanan Cina), dsb. Penulisan cerita wayang ada yang berbentuk prosa (gancaran), puisi (tembang), maupun drama (berbentuk pakem atau pedoman pementasan). Cerita wayang yang bersumber dari luar (India atau Cina) pada umumnya telah diubah untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada di Jawa. b) Menak Sastra Menak bersumber pada Serat Menak. Serat Menak merupakan wiracarita ke-Islaman yang berkembang populer di Jawa, yang menceritakan tokoh utama Wong Agung Menak atau Bagindha Ambyah. Wiracarita ke- 61 Islaman yang lain, misalnya Serat Iskandar dan Serat Yusuf, pada umumnya diimpor sebagai babon cerita kesenian kethoprak, sejenis wayang. Sebelum berkembang di Jawa, Sastra Menak berkembang di Melayu dengan judul Hikayat Amir Hamzah. Cerita ini terbukti berasal dari Persi. Di Jawa, tokoh Amir Hamzah dianggap sebagai tokoh Jawa dengan sebutan Menak. Di sisi lain, Menak juga merupakan sebutan untuk bangsawan di Jawa Timur yakni di daerah Blambangan dan Lumajang. Legenda tokoh-tokoh lokal di Jawa Timur sebagiannya menggunakan nama Menak, yakni Menak Sangkan, Menak Prasanta, Menak Sopal, Menak (Minak) Jingga, dan Menak Supetak. Pada awal abad ke-17 ditengarai telah terdapat naskah Jawa tentang Amir Hamzah yang berupa lontar sebanyak 119 lembar, yang oleh Andrew James diserahkan ke Bodleian Library pada tahun 1627. Selanjutnya terdapat naskah Serat menak yang berasal pada jaman Kartasura berangka tahun 1639 Aj atau tepatnya bulan Juli 1715, milik Kanjeng Ratu Mas Balitar, isteri Pakubuwana I. Serat Menak ini masih tampak jelas berinduk pada naskah Melayu. Serat Menak Kartasura ini panjangnya hanya seperlima Serat Menak Yasadipura. Pada jaman Surakarta dan Yogyakarta, pada kedua kerajaan, yakni Kasunanan dan Kasultanan, sama-sama menyadur teks Menak. Di Surakarta teks Menak diketemukan berupa Serat Menak gubahan Yasadipura II. Adapun di Yogyakarta juga ditemukan cerita Menak berjudul Serat Sujarah Darma, berangka tahun 1720 AJ atau 1794 M. Serat Menak Yasadipura terbagi dalam episode-episode seakan sebagai lakon-lakon, sedangkan Serat Sujarah Darma mirip Serat Menak Kartasura, tidak terbagi dalam episode-episode. Episodeepisode yang ada dalam Serat Menak Yasadipura adalah: Menak Sarehas, Menak Lare, Menak Jobin, Menak Mesir, Menak Kanjun, Menak Sathit, Menak Blanggi (Gulangge), Menak Jamin Ambar, Menak Jenggi, Menak Lakad, Menak Malebari, Menak Bahman dan Menak Sathit Rengganis (Sedyawati, dkk, ed. : 317- 322). Ph.S. van Ronkel pernah membandingkan Serat menak dengan Hikayat Amir Hamzah, dan berkesimpulan bahwa Serat Menak merupakan saduran Hikayat Amir Hamzah berbahasa Melayu, namun dengan tambahan yang terlalu banyak sehingga jalan ceritanya sangat ruwet (Hutomo, 1983: 20). 62 c) Panji Sastra Panji berisi petualangan atau pengembaraan dengan motif percintaan dan penyamaran. Tokoh utamanya bernama Panji Inu Kertapati yang menjalin cinta dengan kekasihnya Galuh Candrakirana, dan ceritanya berhubungan dengan kerajaan Kediri, Jenggala, Gegelang dan Singasari di Jawa Timur. Cerita Panji semula berbentuk kidung (berbahasa Jawa Tengahan), namun kemudian dalam bahasa Jawa Baru berkembang, baik dalam bentuk tembang macapat maupun gancaran, baik dalam saduran tertulis, dalam bentuk lisan, maupun dipergelarkan sebagai drama wayang Panji maupun drama ketoprak. Menurut Poerbatjaraka, cerita Panji berlatar belakang kerajaan Kediri. Panji Inu Kertapati adalah raja Kameswara di Kediri. Cerita Panji ditulis ketika ingatan orang tentang Singasari memudar dan samar-samar, sehingga diceritakan bahwa Singasari sejaman dengan Kediri dan Daha. Oleh karena itu Poerbatjaraka berpendapat bahwa Panji merupakan cerita asli Jawa yang ditulis paling awal pada kerajaan Majapahit dan terus berlanjut pada masa sesudahnya. Pada intinya cerita Panji menceritakan kisah percintaan Inu Kertapati dengan Candrakirana atau Dewi Sekartaji. Sebelumnya, Panji telah menjalin cinta dengan Angreni, putri Patih Kudanawarsa, namun Angreni bunuh diri sebelum dibunuh oleh utusan kerajaan karena dianggap menghalangi perkawinan Panji dengan Candrakirana. Panji yang bersedih pergi mengembara dan menyamar, sehingga memunculkan berbagai kisah cintanya dengan berbagai gadis dan kisah pertempurannya dengan raja-raja di kerajaan lain. Panji selalu menang. Candrakirana yang bersedih karena ditinggalkan Panji juga berkelana dengan menyamar sebagai lelaki untuk mencari Panji. Akhirnya Panji dapat bertemu dengan Candrakirana dan menjalin perkawinan. Beberapa judul cerita Panji antara lain Panji Jayakusuma, Panji Angreni, Panji Kudanarawangsa, Panji Angronakung, dsb. (Sedyawati, dkk., ed., 2001: 274-279). Dalam bentuk cerita lisan, selain dalam bentuk sastera tulis dengan tokoh utama Panji Inu Kertapati, motif pengembaraan dan pencarian cinta, juga ditemukan pada beberapa cerita, misalnya yang sangat populer adalah cerita Andhe Andhe Lumut dalam kisah cinta tokoh Andhe-andhe Lumut dengan puteri 63 pilihannya, yakni Kleting Kuning yang mendapat penghalang dari tokoh antagonis Yuyu Kangkang. 5. Novel dan Crita Cekak (Cerkak). Jenis novel dan cerkak, sebenarnya bukan hasil klasifikasi dari segi tematik seperti halnya jenis-jenis di atas, tapi dari segi struktur atau bentuk sastranya. Namun demikiaan pada umumnya jenis ini memiliki kesamaan tema yang khas, yakni bercerita tentang kehidupan sehari-hari tokoh-tokoh dari masyarakat awam, dan tidak bersifat istanasentris. Kedua jenis ini merupakan hasil karya sastra Jawa modern yang pada umumnya berbentuk prosa. Jenis novel, dan cerkak merupakan jenis karya sastra Jawa modern yang merupakan hasil pengaruh sastra dan teori sastra Barat. Jenis ini pada mulanya muncul di Jawa sekitar akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20, dalam bentuk yang menekankan dedaktik moral. Novel yang pertama kali dianggap sebagai susastra dan tidak dirusakkan oleh kecenderungan pengajaran secara fulgar pada dedaktik moral adalah Serat Riyanta karya R.B. Sulardi, diterbitkan Balai Pustaka pada tahun 1920 (Ras, 1985: 13). Adapun jenis cerkak baru muncul pada 1935 berjudul Sandhal Jinjit ing Sekaten Sala oleh Sri Susinah (Sedyawati, dkk, ed, 2001: 369) kemudian Netepi Kwajiban karya Sambo (Ras, 1985: 19), keduanya dimuat dalam majalah Panjebar Semangat 2 dan 9 Nopember 1935. Antara jenis novel dan cerkak, dapat dibedakan menurut keeratan alur dan kuantitas temanya. Alur cerkak relatif lebih erat dan temanya hanya satu terpusat pada peristiwa yang dialami oleh tokoh utamanya. Novel, alurnya relatif renggang dan temanya bisa tunggal atau banyak. Namun demikian, pada umumnya lebih banyak dibedakan secara kuantitatif, yakni jumlah kata atau halamannya. Menurut Suparto Brata cerita pendek (sering disingkat cerpen) secara harafiah berarti cerita yang pendek. Pada dasarnya cerpen berupa cerita yang mendasarkan pada ide cerita yang dapat diselesaikan secara singkat. Singkat dalam arti terpenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk membangun dan mengakhiri cerita. Jadi meskipun singkat, cerita tersebut telah sempurna (Prawoto, ed., 1993: 41). 64 Jumlah halaman novel relatif panjang dan cerkak lebih pendek. Dalam majalah, cerkak hanya berkisar 3-7 halaman dan dalam koran harian (ariwarti) lebih pendek lagi. Adapun novel dalam majalah dapat diterbitkan berkali-kali secara bersambung dengan 1-3 halaman setiap terbit. Jenis novel yang terakhir ini yang sering disebut dengan cerita bersambung (cerbung), dan jenis inilah yang lebih produktif dalam sastra Jawa. Oleh karena pengaruh dari Barat, maka nuansa modernisasi dalam novel dan cerkak sangat kentara, baik dari segi kebahasaannya maupun dari isi ceritanya. Di samping itu, jenis novel dan cerkak, disadari ataupun tidak, sangat mempertimbangkan teori strukturalisme, yang menekankan sistem transformasi yang bercirikan keutuhan makna keseluruhan. Keutuhan makna keseluruhan itu ditentukan oleh prinsip komposisi tertentu dan mempertahankan otonomi (lihat pendekatan strukturalisme dalam karya sastra, misalnya dalam Teeuw, 1984). Dengan kata lain, keeratan dan keterjalinan berbagai unsur strukturnya, serta kesatuan maknanya, telah terpantau atau diatur semenjak penyusunan novel atau cerkak yang bersangkutan. Demikian pula kemungkinan keotonomian karya sebagai dunia dalam cerita, juga telah dipertimbangkan, meskipun tidak sepenuhnya demikian. 6. Dongeng dan Jagading Lelembut Dongeng pada sastra Jawa modern semula ditulis dalam bentuk tembang maupun prosa, namun kemudian banyak yang ditulis dengan prosa. Adapun jagading lelembut kebanyakan berbentuk prosa, dan berkembang pesat setelah terbitnya majalah-majalah berbahasa Jawa. Antara jenis dongeng dan jagading lelembut, dari segi panjangnya, pada umumnya bisa dikategorikan sebagai cerkak. Namun juga ada beberapa dongeng dan jagading lelembut yang relatif panjang seperti novel, dan sebagian lagi diselipkan pada cerita-cerita panjang lainnya seperti roman, novel, babad, dsb. Antara dongeng, jagading lelembut, dan cerkak penekanan isinya berbeda. Cerkak biasanya berisi cerita kehidupan manusia sehari-hari. Dongeng berisi cerita ngaya wara, khayal (fantastis) dengan tokoh manusia, binatang, atau benda-benda tertentu. Sedang jagading lelembut, berisi cerita tentang manusia 65 dalam hubungannya dengan dunia hantu (jagading lelembut). Namun demikian juga terdapat jenis cerkak yang menekankan cerita surealisme, misalnya dengan tokoh-tokoh yakni bagian-bagian tubuh manusia yang dapat berbicara sendirisendiri. Dengan demikian, terutama perbedaan cerkak dengan dongeng, dalam beberapa segi, sering kali menjadi sulit ditentukan. Jenis cerkak dan jagading lelembut berkembang dalam majalah-majalah berbahasa Jawa. Hampir setiap terbitan majalah berbahasa Jawa selalu memuat rubrik cerkak dan rubrik jagading lelembut. Cerita jagading lelembut ini diperkirakan memiliki pandhemen (pembaca, pecinta) yang cukup signifikan untuk selalu dimuat dalam setiap terbitan. Adapun jenis dongeng, tidak selalu muncul dalam setiap terbitan majalah, meskipun sebenarnya, dongeng telah ada sejak sastra Jawa Kuna, yakni antara lain dalam cerita Tantrikamandaka. Pada sastra Jawa modern, bentuk dongeng antara lain tercatat Serat Kancil (berangka tahun 1871 AJ), Cariyos Panca Candran (1878 AD), Serat Kancil Kridha Martana (Karya R.P. Naranata, tahun 1909 dan 1910 AD), Peksi Glathik (karya Yasawidagda, 1913 AD), Layang Dongeng Sato Kewan (karya CF Winter, 1930 AD), Serat Kancil Tanpa Sekar ( Padmasusastra, 1931 AD), Dongeng Isi wewulang Becik (1849 AD oleh C.F. Winter), Kancil Kepengin Mabur (S. Suryasubrata, 1951 AD), Dongeng Sato Kewan (Prijana Winduwinata, 1952 AD), dsb. 7. Kisah Perjalanan dan Biografi Kisah Perjalanan dan Biografi merupakan karya sastra prosa atau puisi yang bentuknya seperti novel, novelet atau cerpen, namun isinya semacam laporan perjalanan, biografi atau otobiografi. Karya-karya ini pada umumnya lebih menyerupai bentuk jurnalistik, sehingga estetika fiksinya tidak begitu menonjol. Jenis ini antara lain berjudul Wanagiri karya Mangkunegara IV (1844 AD), Tegalganda karya Mangkunegara IV (1855 AD), Raden Mas Harya Purwalelana (1857 AD), Lampah-lampahanipun RMA. Purwalelana (1866AD), Wanagiri Prangwadanan (1879 AD), Cariyosipun saking Singapura Layar dhateng Kelantan (1883 AD), Serat Cariyos Kekesahan saking Tanah Jawi 66 dhateng Negari Wlandi karya RMA Surya Suparta (1916 AD), Nayaka Lelana karya Susanta Tirtapraja (1955 AD), Sang Prajaka karya Sardono BS (1962 dan 1963 AD), dsb. 8. Primbon Primbon yakni jenis karangan yang berisi catatan kumpulan berbagai keilmuan Jawa, baik yang bersifat logis maupun pralogis, yang juga merupakan kumpulan dari folklor, yakni sejumlah sastra atau budaya lisan, setengah lisan atau bukan lisan. Secara garis besar (Subalidinata, tt.: 7) primbon berisi empat masalah pokok, yakni kelahiran, perkawinan, kematian dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Kata primbon berasal dari pari-imbu-an. Kata imbu berarti ‘simpan’. Jadi primbon dapat berarti ‘simpanan kumpulan catatan’, yakni catatan berbagai keilmuan atau pengetahuan yang ada dalam tradisi masyarakat Jawa. Pada umumnya primbon ditulis dalam bentuk prosa, namun dalam sejumlah permasalahan kadang kala juga berupa puisi, seperti halnya puisi mantera. Yang termasuk pembicaraan dalam primbon antara lain, perbintangan, pengobatan tradisional, perhitungan waktu baik dan buruk, perhitungan struktur dan letak bangunan rumah, katuranggan ( ciri-ciri fisik dan karakteristiknya) untuk binatang piaraan tertentu (kuda, ayam jago, burung perkutut) dan wanita dan sebagainya. Primbon, dalam kekhasannya, dapat dibicarakan dalam rangka pembicaraan sastra, namun juga dapat dibicarakan dalam rangka pengetahuan budaya Jawa. Hal ini dikarenakan isi dan tujuan dituliskannya primbon, yang jelas bukan semata-mata untuk bacaan sebagai susastra (sastra indah), tetapi lebih mengarah pada tuntunan dalam hal tradisi budaya Jawa tertentu. Di atas sudah disinggung tentang sebagian isi dari primbon, yakni antara lain perbintangan atau pawukon, petungan, dsb. Dalam hal perbintangan Jawa yang dihitung dengan hari kelahiran seseorang, di Jawa dikenal adanya istilah wuku. Pengetahuan tentang wuku disebut pawukon. Dalam budaya Jawa wuku berjumlah 30 buah, yakni (1) Wukir, (2) Kuranthil, (3) Tolu, (4) Gumbreg, (5) Warigalit, (6) Warigagung, (7) 67 Julungwangi, (8) Sungsang, (9) Galungan, (10) Kuningan, (11) Langkir, (12) Mandasiya, (13) Julung Pujut, (14) Pahang, (15) Kuruwelut, (16) Marakeh, (17) Tambir, (18) Madangkungan, (19) Maktal, (20) Wuye, (21) Manail, (22) Prangbakat, (23) Bala, (24) Wugu, (25) Wayang, (26) Kelawu, (27) Dhukut, (28) Watugunung, (29) Sinta, dan (30) Landhep. Timbulnya pawukon, bersumber dari cerita tentang Prabu Watugunung. Yang singkatnya sebagai berikut. Prabu Watugunung, raja di Gilingwesi mempunyai dua permaisuri, yakni Dewi Sinta dan Landhep. Ketika Dewi Sinta sedang mencari kutu di kepala Prabu Watugunung, ia melihat bekas luka di kepala itu. Ketika ditanyakan, Prabu Watugunung mengisahkan bahwa dulu baginda pernah dipukul oleh ibunya dengan centong nasi. Maka ingatlah Dewi Sinta, bahwa kisah itu adalah kisahnya beserta anak laki-lakinya, dan sadarlah bahwa ia telah menikah dengan anaknya sendiri. Dewi Sinta bermaksud memisahkan diri dengan sang Raja, dengan cara memohon pada sang Raja untuk kawin dengan bidadari. Maka berangkatlah Prabu Watugunung ke Kahyangan untuk melamar bidadari. Akhirnya Prabu Watugunung tewas oleh Dewa Wisnu. Sinta bersedih atas kematian itu dan memohon kepada para dewa agar menghidupkan kembali. Ternyata Prabu Watugunung tidak bersedia, dan justru memohon agar para dewa mengambil keluarganya naik ke surga agar dapat bersatu dengannya. Akhirnya pengambilan keluarga itu dilakukan satu-persatu pada tiap tujuh hari sekali. Waktu tujuh hari itulah yang kemudian menjadi hitungan satu wuku. Dengan demikian, satu wuku berumur tujuh hari, sehingga 30 wuku lamanya 210 hari. Pada saat ini, wuku Galungan dan Kuningan masih sering dipergunakan dalam hubungannya dengan hari besar agama Hindu, terutama di Pulau Bali. Di samping berisi tentang pawukon, primbon juga berisi tentang petungan dina (perhitungan hari) yakni hari baik dan hari buruk dalam hubungannya dengan keperluan atau hajatan tertentu. Saat yang buruk disebut naas, dan sebaiknya tidak dilakukan sesuatu pada hari naas tersebut, karena menurut kepercayaan akan membawa petaka atau kecelakaan tertentu. 68 Perhitungan hari yang masih sering berlaku yakni pancawara (pembagian waktu ke dalam lima hari ) dan saptawara (pembagian waktu ke dalam tujuh hari ). Penamaan pancawara adalah: (1) Legi (Manis), (2) Pahing (Abritan), (3) Pon (Kuningan), (4) Wage (Cemengan), dan (5) Kliwon (Kasih). Adapun penamaan hari menurut saptawara adalah (1) Ahad (Dite), (2) Senin (Soma), (3) Selasa (Anggara), (4) Rabu (Budha), (5) Kamis (Respati), (6) Jumat (Sukra), dan (7) Sabtu (Tumpak). Ada lagi perhitungan hari yang disebut paningkelan dan padewan. Termasuk dalam paningkelan, yakni: (1) Tungle, (2) Aryang, (3) Wurukung, (4) Paningron, (5) Uwas, dan (6) nawulu. Karena perhitungan 6 hari maka juga disebut sadwara. Sedang yang termasuk dalam padewan, yakni: (1) Sri, (2) Endra, (3) Guru, (4) Yama, (5) Lodra, (6) Brahma, (7) Kala, dan (8) Uma. Karena memuat 8 hari, maka juga disebut asthawara. Masih ada lagi perhitungan hari dalam 10 hari yang disebut dasawara, yang meliputi: (1) Sri, (2) Manu, (3) Manusa, (4) Radiya, (5) Ditya, (6) Raksasa, (7) Danidya, (8) Pisatya, (9) Dewa, dan (10) Yaksa. Nama bulan dalam sastra dan budaya Jawa yakni (1) Sura, (2) Sapar, (3) Mulud, (4) Bakdamulud, (5) Jumadilawal, (6) Jumadilakir, (7) Rejeb, (8) Ruwah, (9) Pasa, (10) Sawal, (11) Dulkaidah, dan (12) Besar. Terdapat perhitungan musim dalam satu tahun. Nama-nama musim adalah (1) Kasa (Srawana), (2) Karo (Badra), (3) Katelu (Asuji), (4) Kapat (Kartika), (5) Kalima (Margasira), (6) Kanem ( Posya), (7) Kapitu (Magha), (8) kawolu (Phalguna), (9) Kasanga (Cetro), (10) Kasapuluh (Wesaka), (11) Desta (Jyetha), dan (12) Sadda (Asadha). Nama-nama tahun dalam sastra dan budaya Jawa yakni (1) Alip, (2) Ehe, (3) Jemawal, (4) Je, (5) Dal, (6) Be, (7) Wawu, dan (8) Jemakir. Setiap delapan tahun tersebut disebut satu windu. Nama windu ada 4 buah, yakni (1) Adi, (2) Kuthara, (3) Sangsara, dan (4) Sancaya. Dalam hubungannya dengan pengobatan tradisional terhadap penyakit tertentu, atau keadaan buruk tertentu, atau untuk mencegah (preventif) kondisi buruk tertentu, sering kali primbon menawarkan solusi, yakni dengan meramu obat tertentu atau membuat sajen-sajen (sesaji) tertentu, dan sebagiannya dengan 69 menyertakan mantera-mantera tertentu, baik yang bentuknya panjang maupun yang relatif pendek. Sebagian mantra-mantra ini, dari beberapa segi dapat dianggap sebagai karya sastra yang berbentuk puisi atau prosa liris. Sebagai contoh, bagi ibu yang sedang hamil atau suaminya, bila melihat atau menemukan sesuatu yang aneh harus mengucapkan : Jabang bayi aja kaget yang berarti ‘anak bayi jangan kaget’. Contoh lainnya, bila akan tidur harus membasuh kaki dengan air garam dan mengucapkan mantra: Singgah-singgah kala singgah, kang abuntut, kang ngawulu, kang ngajoto, kang ngasiyung, padha sira suminggaha, aja wuruk sudi gawe, ingsun wus weruh ajal kamulanira (Mahadewa, 1993: 110), kurang lebih artinya ‘kembalilah ke sarangmu hai Kala kembalilah, yang berekor, yang berbulu, yang tubuhnya menonjol, yang bertaring, kalian semua kembalilah, jangan suka menggangguku, karena aku sudah tau rahasia kematianmu”. Namun demikian, tidak banyak mantera yang dapat diterjemahkan atau dimengerti arti kata-katanya. Hal ini dikarenakan yang ditekankan dalam bentuk mantera adalah penghayatannya, yakni kepercayaan dan proses atau langkah (laku) yang harus dijalaninya. 10) Jenis sastera lainnya masih banyak, tetapi relatif tidak populer, seperti jenis silsilah (sarosilah), surat-surat, religi, kamus, dsb. B. Jenis-jenis Sastra Jawa Modern Berdasarkan Bentuknya Seperti telah disinggung di atas, karya sastra berdasarkan bentuknya, secara sederhana dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yakni karya sastra prosa, puisi dan drama. Sesungguhnya klasifikasi berdasarkan bentuknya semacam ini hanyalah sekedar mempermudah pembatasan pembicaraanya agar kerangka berpikirnya tidak terlalu luas. Pada kenyataan di lapangan, ditemukan karyakarya yang berada di antara dua jenis atau bahkan di antara tiga jenis. Hal itu perlu disampaikan di sini agar jangan sampai mengarahkan pada cara berpikir yang kaku bertumpu pada pola-pola jenis tertentu, mengingat pemaknaan karya sastra dapat dilakukan dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian secara sederhana, berdasarkan bentuk penulisannya, sastra Jawa modern juga dapat diklasifikasikan ke dalam jenis prosa, puisi dan drama. 70 Jenis prosa dalam bahasa Jawa sering disebut gancaran. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa jenis ini bercirikan penekanannya pada ceritaan atau narasi dengan bahasa yang berupa kalimat-kalimat formal. Adapun jenis puisi, secara sederhana bercirikan penekanannya pada diksi atau pilihan kata, dan disajikan dengan bahasa estetis yang biasanya tertulis dalam larik-larik Sedangkan jenis drama menekankan pada teknik lakuan dan dialog-dialog yangmembentangkan alur. 1. Sastra Prosa Jawa Modern Prosa, bila klasifikasinya didasarkan pada penekanan adanya alur atau narasi, atau dengan kata lain prosa itu identik dengan narasi, maka dalam sastra Jawa menjadi ambigu. Hal ini dikarenakan banyak karya sastra Jawa yang berjenis naratif tetapi disusun dalam bentuk tembang. Padahal, bentuk tembang pada umumnya dikategorikan sebagai puisi. Sebagai contoh adalah karya roman pewayangan banyak yang dikisahkan melalui bentuk tembang macapat. Demikian pula sastra babad yang notabene berisi sejarah (narasi, kisahan), juga banyak yang ditulis dalam bentuk tembang macapat. Oleh karena itu yang dimaksud prosa di sini, dikhususkan pada jenis sastra prosa Jawa modern yang dalam istilah Jawa sering disebut sebagai jenis gancaran. Jenis gancaran ditandai dengan struktur bahasa Jawa formal konvensional yang dari segi linguistik cenderung mempertimbangkan struktur subyek (jejer) predikat (wasesa)- dan obyek (lisan). Disamping itu tidak memperhatikan berbagai aturan dalam hubungannya dengan bait-bait, baris-baris, atau bunyibunyi persajakan tertentu. Dalam khasanah sastra Jawa banyak karya sastra yang ditulis dalam bentuk tembang yang kemudian ditulis kembali dalam bentuk gancaran, atau sebaliknya dari bentuk gancaran ditulis kembali dalam bentuk tembang. Dengan demikian, dari segi isinya jenis prosa gancaran tidak banyak berbeda dengan yang berjenis puisi. Oleh karena itu sastra prosa Jawa modern pada dasarnya juga telah menghasilkan tema-tema yang telah disebutkan diatas, yakni sejarah, ajaran, wiracarita (wayang dan sebagainya), mistik, dongeng, hantu (jagading lelembut), primbon, cerkak, novel, dan sebagainya. 71 a. Sekilas Perkembangan Sastra Prosa Jawa Modern Dari sisi perkembangannya, pada mulanya bentuk-bentuk karya sastra prosa Jawa modern relatif miskin, sebagian hasil karya prosa yang ada, nilai susastranya dan tingkat kefiksiannya kurang. Hal ini antara lain disebabkan sebagai berikut. Pertama, semula karya sastra Jawa modern pada umumnya ditulis dalam bentuk puisi berupa tembang gedhe, tembang tengahan dan tembang macapat. Karya-karya yang sering digolongkan dalam sastra Jawa modern atau berbahasa Jawa baru, tetapi bersifat tradisional, adalah karya-karya dalam bentuk tembang ini, terutama pada jenis-jenis yang berisi babad, niti, wayang, dan suluk. Jenisjenis ini pada abad ke-20 sudah jarang diproduksi, bahkan relatif sedikit yang direproduksi, baik dalam bentuk cetak maupun carik (tulisan tangan). Kedua, bentuk prosanya, semula atau sebelum abad ke-20-an, terbatas, seperti halnya hasil karya primbon, jurnalistik, baik dalam bentuk laporan perjalanan maupun biografi tokoh-tokoh tertentu atau jenis lainnya, surat-surat pribadi dan beberapa jenis lainnya yang tidak begitu populer. Ketiga, hasil karya prosanya berupa bangunan kembali dari karya sastra yang telah ada yakni karya-karya versi prosa dari beberapa karya sastra Jawa klasik (istilah J.J. Ras) yang kebanyakan semula ditulis dalam bentuk tembang gedhe, tembang tengahan atau tembang macapat. Keempat, karya-karya prosa yang muncul sebelum tahun 1900-an, sangat menekankan dedaktik atau ajaran moral, yang dari satu sisi, oleh J.J.Ras (1985: 13) dinilai merusakkan (estetika), sehingga tampak keindahan bentuknya tidak terlalu dipertimbangkan karena lebih menekankan isinya. Bentuk prosa sebagaimana karya prosa yang merupakan hasil pengaruh dari sastra Barat, yakni novel, novelet dan cerita pendek, pada akhir abad ke-19 masih asing dan langka. Karya sastra prosa Jawa yang bentuknya novel atau protonovel baru tercatat karya R. Ng. Ranggawarsita yakni Serat Witaradya. Kemudian pada tahun 1909, R. Martadarsana menulis Topeng Mas I dan Topeng Mas II. Selanjutnya Ki Padmasusastra menulis berjudul Serat Rangsang Tuban berupa novel kebatinan (Surakarta, 1912). Bentuk novel awal lainnya, karya 72 Pakubuwana X dan R. Ng. Purbadipura, berjudul Srikarongron. Kemudian R. Ng. Mangunwidjaja, taun 1916 menulis Serat Trilaksita, dan Koeswadihardja menulis Serat Tjarijosipun rara Kadreman. Awal mula perkembangan novel tidak terlepas dari peranan munculnya penerbit Balai Pustaka. J.J. Ras (1985: 8-17) mencatat hasil-hasil karya sastra yang dimotori oleh penerbit tersebut dan beberapa lembaga swasta. Dari hasilhasil yang tercatat semula, yakni pada dasawarsa pertama abad ke-20 , antara lain berupa buku-buku kecil dan dengan halaman yang relatif pendek, beisi ajaranajaran moral yang ditulis secara fulgar, belum memperhitungkan keindahan permainan unsur-unsur struktur fiksi. Pada tahun 1920 terbitlah Serat Riyanta karya R.B. Sulardi yang merupakan novel Jawa awal yang relatif bagus. J.J. Ras mencatat bahwa buku ini merupakan buku pertama yang tidak dirusakkan oleh kecenderungan didaktik atau ajaran moral, yang berisi kisah dengan alur yang benar-benar bagus yang dibangun di sekitar tema yang jelas pula. Temanya dikaitkan dengan masalah sosial, yakni pemberontakan generasi muda terhadap perkawinan adat yang banyak dilalui oleh para orang tua dengan cara menjodohkan anak-anaknya. Setelah terbitnya novel Serat Riyanta, lalu bermunculan karya sastra berbentuk novel atau novelet. Pada sekitar tahun 1960-an, demi memenuhi tuntutan keperluan bacaan masyarakat, banyak muncul novel-novel yang sangat pendek (novelet), diterbitkan dalam bentuk stensilan menjadi buku kecil-kecil dan tipis-tipis, dengan tema-tema percintaan dan banyak dibumbui oleh adeganadegan cremedan (berbau porno), setidak-tidaknya dari kacamata para pembaca jaman munculnya karya-karya yang bersangkutan. Dewasa ini novel-novel Jawa pada umumnya berisi ceritera kehidupan sehari-hari pada masyarakat modern saat ini, yang tidak bersifat istanasentris. Karya cerita pendek Jawa yang dikenal dengan nama cerkak (crita cekak) mulai muncul pada tahun 1935 dalam majalah berbahasa Jawa Panjebar Semangat oleh Sambo dengan judul Netepi Kwajiban, dan tahun 1936 dalam majalah Kejawen (Ras, 1985: 18). Jenis ini muncul dalam hubungannya dengan keperluan praktis untuk mengisi kolom dan halaman majalah berbahasa Jawa, 73 sehingga kebanyakan ditulis oleh anggota redaksi majalah yang bersangkutan. Tidak berlebihan bila ditulis dengan anonim atau dengan nama samaran. Dewasa ini jenis cerkak banyak ditulis oleh para cerpenis Jawa dan tidak terbatas pada mereka yang duduk di meja redaksi majalah. Dari segi isinya, jenis cerkak mampu menampung tema-tema yang lebih luas daripada jenis novel. Jenis cerkak ini dapat menceritakan kehidupan sehari-hari para tokohnya, hingga kehidupan dunia fantasi, dapat bersifat realis dan dapat juga surealis. Pada perkembangan tertentu, muncul karya prosa yang mengetengahkan tema tertentu, yang akhirnya berkembang menjadi jenis tersendiri, yakni jagading lelembut. Seperti telah disinggung di atas, Jagading lelembut, adalah cerita yang mengisahkan tokoh manusia dalam hubungannya dengan dunia hantu. Cerita semacam itu dari sisi tertentu dapat dikategorikan sebagai dongeng. Dalam khasanah sastra Jawa, jagading lelembut berkembang secara khas yakni melalui kolom-kolom atau halaman-halaman dalam rubrik majalahmajalah berbahasa Jawa dalam bentuk mirip seperti cerkak atau cerita bersambung. Pada mulanya rubrik jagading lelembut dimaksudkan untuk menampung kisah-kisah nyata yang dialami atau terjadi di masyarakat. Pada perkembangannya, jagading lelembut tidak harus berisi kisah nyata, atau kisah nyata yang telah diberi berbagai tambahan bersifat fiktif agar lebih menarik. Jenis sastra dongeng Jawa, dalam arti luas, kadang-kadang muncul dalam rubrik majalah berbahasa Jawa, baik untuk bacaan anak-anak (dongeng bocah) maupun untuk umum. Pada perkembangan terakhir karya-karya novel juga lebih banyak terbit dalam terbitan majalah-majalah berbahasa Jawa, yakni dalam bentuk cerita bersambung. Demikian pula jenis cerpen Jawa (cerkak), terutama hidup sebagai sastra majalah. Oleh karena itu beberapa kalangan mengklaim bahwa karya sastra Jawa modern tergantung pada kehidupan majah berbahasa Jawa. Mereka menyebut karya sastra Jawa modern sebagai sastra majalah. Hal tersebut di atas, ada benarnya, namun juga tidak sepenuhnya benar. Hal ini ditandai dengan masih munculnya beberapa novel Jawa pada dekade terakhir ini. Di samping itu, pada waktu-waktu tertentu juga muncul lombalomba penulisan sastra Jawa, baik dongeng, cerkak atau novel. Pada umumnya, 74 hasil dari lomba-lomba inilah yang kemudian juga diterbitkan dalam bentuk buku novel atau antologi dongeng atau cerkak. b. Kekhasan Jenis Prosa Jawa Modern dan Kemungkinan Pendekatannya Yang perlu diperhatikan dalam perkembangan prosa Jawa modern, adalah konteks sastra yang muncul pada masa-masa tertentu. Setiap jenis sastra memiliki kekhasannya masing-masing yang sebagiannya dikarenakan konteks sosial budaya masing-masing yang berbeda-beda. Tulisan ini tidak bermaksud mendikte atau menggariskan secara pasti, namun hanya merupakan catatan secara umum yang dengan sendirinya dapat saja berbeda dengan kenyataan khusus di lapangan. Pada jenis kisah perjalanan, jenis biografi, dan sastra dedaktik moral, tentu saja masalah permainan unsur-unsur strukturalnya tidak begitu ditekankan, namun lebih mementingkan tema dan amanatnya. Dengan demikian pendekatannya cenderung secara tematik, pragmatik atau filosofis ke arah moral dan sosial. Pada karya-karya prosa yang merupakan bangunan kembali dari karyakarya sebelumnya, tentu saja hasil kecermatan studi banding sangat diperlukan, baik secara filologis, intertekstual maupun perbandingan tematik. Melalui perbandingan dengan naskah-naskah sebelumnya atau sumbernya, tentu didapatkan kejelasan makna secara lebih memadahi, baik dalam hubungannya dengan amanat yang ditawarkan oleh penyalin, maupun dalam hubungannya dengan pandangan masyarakat tertentu pada era tertentu. Pada jenis jagading lelembut dan dongeng lainnya, tentu saja dapat diterapkan pendekatan seperti yang dilakukan pada jenis-jenis folklore. Dengan demikian pengkajian motif-motif tertentu atau tema-tema tertentu, pengkajian jenis-jenis tokoh tertentu, pengkajian fungsi terhadap masyarakatnya atau latar belakang budayanya sangat diperlukan. Adapun pada jenis-jenis sastra prosa yang merupakan hasil pengaruh dari jenis sastra dan teori sastra Barat, baik novel, novelet, maupun cerkak, sifat permainan unsur-unsur strukturalnya sangat penting untuk diperhatikan. Dengan demikian pendekatan formal harus ditekankan dan dibutuhkan pengetahuan 75 tentang teori struktural untuk mendekatinya, sebelum dikembangkan pada pengkajian yang lain. c. Unsur-unsur Struktur Sastra Prosa Jawa Modern Unsur-unsur struktur sastra, khususnya sastra prosa Jawa modern, tidak berbeda dengan unsur-unsur yang ditemukan pada karya-karya sastra prosa pada umumnya, yakni yang menyangkut unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsurunsur intrinsik, yakni unsur-umsur yang membangun struktur sastra itu sendiri atau secara langsung membangun cerita. Adapun unsur ekstrinsik adalah unsurunsur yang berada di luar karya sastra itu, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi bangunan atau organisme karya sastra (Nurgiyantoro, 1995: 23). Pemahaman unsur ekstrinsik akan membantu dalam hal pemahaman karya sastra, karena terciptanya karya sastra tidak berasal dari situasi kekosongan budaya. Unsur-unsur ekstrinsik antara lain visi dan misi pengarang, lingkungan alam dan lingkungan sosial pengarang, termasuk ekonomi dan politik yang terjadi, dsb. Pada kenyataannya sering kali pemisahan antara unsur intrinsik dan ekstrinsik menemui kesulitan. Hal ini terutama dikarenakan bahasa, sebagai sarana sastra, mengandung bentuk dan isi sekaligus. Dari segi bentuknya, bahasa menyampaikan informasi seperti apa yang ada dalam kata atau frasa atau kalimat dst. yang ada dalam bahasa itu. Dari segi isinya, informasi yang ada itu sering kali bersifat tidak eksplisit atau simbolis, yang pemaknaannya harus dicari dari latar belakang sosial budayanya. Di samping itu, antara bahasa dan sastra samasama merupakan sistem semiotik (simbol makna) yang kadang-kadang tidak jelas batas-batasnya. Dengan kata lain, dalam menguraikan unsur-unsur intrinsik sering kali harus menengok ke latar belakang sosial budaya pengarang maupun pembacanya, sehingga mau tidak mau harus mencari unsur-unsur ekstrinsiknya. Sebagai contoh konkrit, dalam menguraikan penokohan, sering kali orang harus berangkat dari sistem nilai etika dan moralitas yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan. Bila dalam sastra Jawa dinyatakan bahwa seorang pria akan dan harus memilih calon istrinya dengan mempertimbangkan bobot, bibit, bebet dan dalam karya sastra yang bersangkutan istilah itu tidak pernah dijelaskan lagi, 76 maka konsep bobot, bibit, bebet tersebut harus dicari penjelasannya dari konteks sosial budaya Jawa. Dan sebagainya dan sebagainya. Unsur-unsur intrinsik yang membangun sastra prosa atau prosa fiksi antara lain peristiwa, cerita, plot, penokohan, tema, latar, sudut pandang penceritaan, bahasa atau gaya bahasa, dan sebagainya (Nurgiyantoro, 1995). Stanton (1965; via Suwondo, 1994) juga mendeskripsikan unsur-unsur struktur fiksi yang terdiri atas tema, fakta cerita, dan sarana sastra. 1) Tema Tema adalah sesuatu yang menjadi dasar cerita. Ia selalu berkaitan dengan berbagai pengalaman kehidupan, seperti masalah cinta, kasih, rindu, takut, maut, religius, dan sebagainya. Dalam hal tertentu, sering tema dapat disinonimkan dengan ide atau tujuan utama cerita (Tentang tema dan klasifikasinya lihat: Nurgiyantoro, 1995, Oemarjati, 1962; Hutagalung 1967, dsb.). 2) Fakta Cerita Fakta cerita yang meliputi alur, tokoh dan latar, merupakan unsur fiksi yang secara faktual dapat dibayangkan peristiwanya, eksistensinya, dalam sebuah novel (fiksi). Oleh karena itu ketiganya juga disebut struktur faktual (factual structure) atau derajat faktual (factual level) sebuah cerita. Ketiga unsur tersebut harus dipandang sebagai satu kesatuan dalam rangkaian keseluruhan cerita, bukan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri dan terpisah satu dengan yang lain. a) Plot (Alur) Alur sering disebut juga plot cerita, sering juga disebut struktur naratif atau sujet. Dalam hal ini yang harus dicermati ialah bahwa plot bukan sekedar jalan cerita atau urutan peristiwa secara kronologis, namun rangkaian peristiwa yang ditandai dengan hubungan sebab-akibat. Hal ini misalnya pernah dikemukakan oleh Stanton, oleh Forster, dsb. Menurut Stanton (1965: 14, via Nurgiyantoro, 1995) plot adalah cerita yang berisi urutan kejadian, namun tiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab-akibat, peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain. Senada dengan itu 77 Forster juga menyatakan bahwa plot adalah peristiwa-peristiwa cerita yang mempunyai penekanan pada adanya hubungan kausalitas (bdk Oemarjati, 1962: 94; Lubis, 1960: 16) Menurut Forster (via Nurgiyantoro, 1995) plot memiliki sifat misterius dan intelektual. Misterius maksudnya bahwa dalam plot itu belum tentu langsung diselesaikan secara cepat tapi sedikit demi sedikit, atau peristiwanya sengaja dipisahkan pada bagian yang berjauhan urutan penceritaannya, atau ditunda pengungkapan kunci permasalahannya, atau justru dibalik urutan waktu kejadiannya. Hal yang demikian itu yang menimbulkan keingintahuan pembaca untuk membaca terus karya sastra yang bersangkutan hingga selesai. Harapan dan rasa ingin tahu pembaca terhadap kelanjutan plot yang misterius itu sering disebut suspense. Sedang yang dimaksud dengan intelektual ialah bahwa dalam plot terkandung logika tentang hubungan sebab akibat yang harus disikapi dengan intelek dan kritis oleh pembaca agar pembaca yang bersangkutan mampu memahami permainan plot pada karya sastra yang dibacanya. Dalam hubungannya dengan analisis struktural justru permainan plot itu harus dijelaskan secara rinci sehingga dapat dengan mudah dijelaskan hubungannya dengan anasir-anasir selain plot dalam rangka pemahaman makna secara keseluruhan. Membicarakan plot pada dasarnya membicarakan tentang berbagai peristiwa dan konflik. Yang disebut peristiwa ialah peralihan dari keadaan yang satu kepada keadaan yang lain. Peristiwa, setidak-tidaknya dapat dibagi menjadi tiga, yakni peristiwa fungsional, kaitan dan acuan. Peristiwa fungsional merupakan peristiwa yang menentukan dan atau mempengaruhi perkembangan alur atau plot. Peristiwa kaitan adalah perstiwa-peristiwa yang mengaitkan antar peristiwa-peristiwa penting (fungsional) dalam pengurutan plot. Sedang peristiwa acuan merupakan peristiwa-peristiwa yang tidak berpengaruh secara langsung terhadap perkembangan alur, tetapi mengacu pada unsur-unsur lain, misalnya watak tokoh, suasana yang berpengaruh pada watak tokoh, dsb (Luxemburg, dkk.1989). Nurgiyantoro mencatat bahwa anatar peristiwa itu di samping mempunyai hubungan logis juga mempunyai sifat hierarkhis logis, tingkat kepentingannya, 78 keutamaannya, atau fungsionalitasnya. Roland Barthes menyebut peristiwa yang dipentingkan atau diutamakan sebagai peristiwa utama atau peristiwa mayor; sedang yang tidak dipentingkan disebut peristiwa minor atau peristiwa pelengkap. Senada dengan itu Chatman menyebut peristiwa utama sebagai kernel, sedang peristiwa pelengkap sebagai satelit (Nurgiyantoro, 1995: 120). Perbedaan peristiwa-peristiwa tersebut akan tampak jelas bila sebuah karya fiksi diringkas (Luxemburg, dkk, 1989). Semakin tidak penting peristiwa itu akan semakin besar kemungkinannya untuk tidak dituliskan kembali dalam ringkasan. Konflik menyaran pada sesuatu yang tidak menyenangkan yang terjadi dan atau dialami oleh tokoh cerita. Bila tokoh itu memiliki kebebasan untuk memilih, maka ia tidak akan memilih peristiwa itu menimpa dirinya (Meredith & Fitzgeralt, via Nurgiyantoro, 1995). Konflik adalah sesuatu yang dramatik, mengacu pada pertarungan antara dua kekuatan yang seimbang dan menyiratkan adanya aksi dan aksi balasan (Wellek & Warren, via Nurgiyantoro, 1995). Peristiwa dan konflik biasanya berkaitan erat, dapat saling menyebabkan terjadinya satu dengan yang lain, bahkan konflik pun pada hakikatnya merupakan peristiwa. Konflik dapat dibagi menjadi dua, yakni konflik internal (konflik kejiwaan) dan konflik eksternal. Konflik internal terjadi dalam diri seorang tokoh, sedang konflik eksternal terjadi antara tokoh dengan lingkungannya, yakni tokoh(-tokoh) lain atau lingkungan alam. Konflik juga dapat dibagi menjadi konflik batin dan konflik fisik (Nurgiyantoro, 1995). Di samping itu berdasarkan fungsinya konflik juga bisa dibagi menjadi konflik utama dan konflik pendukung (konflik tambahan). Dengan demikian bisa didapatkan konflik utama internal, konflik utama eksternal, konflik pendukung internal dan konflik pendukung eksternal. Dalam fiksi sering terjadi pertemuan antar berbagai konflik sehingga konflik itu semakin meningkat. Bila konflik meningkat hingga mencapai tingkat intensitas tertinggi maka keadaan itu disebut klimaks. Klimaks merupakan pertemuan antara dua (atau lebih) hal (keadaan) yang dialami oleh tokoh-tokoh utama, yang dipertentangkan, dan yang menentukan bagaimana permasalahan (konflik) pada tokoh-tokoh utama itu akan diselesaikan (Nurgiyantoro, 1995). 79 Ditinjau dari segi keberhasilannya, struktur plot setidak-tidaknya harus memperhatikan plausibilitas, suspense, surprise, dan kesatupaduan plot, serta menghindari deus ex machina. Plausibilitas maksudnya bahwa plot harus dapat dipercaya atau diterima dari segi logika cerita. Dalam hal ini tidak harus berarti bahwa cerita itu harus realis sesuai dengan keadaan pada dunia nyata, tetapi lebih mengacu pada sifat koheren dan konsisten pada sebab-akibat dalam plot. Misalnya, logika cerita untuk novel realis tentu berbeda dengan novel surealis atau cerita jagading lelembut. Bila tokoh Gathutkaca bisa terbang bukan berarti alur cerita itu tidak memenuhi konsep plausibilitas. Tapi bila Gathutkaca tidak bisa terbang, justru itulah yang harus dicari alasannya dan plausibilitasnya. Apabila suatu cerita secara tiba-tiba, tanpa diberikan alasan yang jelas, dimunculkan dengan cara kebetulan (Jw: ndilalah) dan dipaksakan sebagai alasan untuk mengembangkan cerita selanjutnya atau untuk menyelesaikan permasalahan hingga tampak tidak masuk akal, maka alasan itu disebut sebagai deus ex machina. Adanya deus ex machina mengurangi kadar plausibilitas pada plot karya sastra. (Nurgiyantoro, 1995) Suspense atau sering disebut tegangan menyaran pada perasaan kurang pasti terhadap peristiwa-peristiwa yang akan terjadi atau harapan yang belum pasti terhadap akhir cerita Suspense harus dibangun dan dipertahankan dalam plot untuk memotivasi, menarik dan mengikat pembaca agar tetap setia menyelesaikan bacaannya karena penasaran. Salah satu cara untuk membangkitkan suspense ialah dengan cara memunculkan foreshadowing dalam cerita. Foreshadowing adalah bagian cerita yang dapat dipandang sebagai pertanda atau isyarat akan terjadinya sesuatu dalam cerita selanjutnya. Bagi orang Jawa, misalnya menampilkan peristiwa “ketiban cecak” sebagai isyarat akan terjadinya musibah pada tokoh yang kejatuhan cicak itu (Nurgiyantoro, 1995). Di samping suspense, plot sebaiknya juga mengandung surprise atau kejutan. Plot sebuah karya fiksi dikatakan memberikan kejutan jika sesuatu yang dikisahkan atau kejadian-kejadian yang ditampilkan menyimpang atau bertentangan dengan harapan pembaca (Abrams, via Nurgiyantoro, 1995). Dalam hal ini sebenarnya tekanannya pada plot itu sendiri dalam kaitannya dengan sebab-akibat. Sebagai contoh pada fiksi ditektif, biasanya memberikan surprise 80 pada menjelang akhir kisah, yakni pembunuh atau terdakwanya biasanya orang yang, oleh pembaca, tak terduga sama sekali. Mungkin orang terdekat korban yang pada beberapa hal ditampilkan baik budi, namun pada hal-hal tertentu bisa berbuat buruk dan jahat. Antara suspense, surprise dan plausibilitas harus berjalinan erat, dan saling menunjang -mempengaruhi serta membentuk satu kesatuan yang padu. Surprise, walaupun mengejutkan tetapi harus tetap bisa dipertanggungjawabkan logika sebab akibatnya, agar tidak menjadi deus ex machina (Nurgiyantoro, 1995). Plot juga harus memiliki kesatupaduan atau keutuhan atau unity. Kesatupaduan menyaran pada pengertian bahwa berbagai unsur yang ditampilkan, khususnya peristiwa-peristiwa fungsional, kaitan dan acuan, yang mengandung konflik, atau seluruh pengalaman kehidupan yang hendak dikomunikasikan, mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain. Ada benang merah yang menghubungkan berbagai aspek cerita sehingga seluruhnya dapat terasakan sebagai satu kesatuan yang utuh padu (Nurgiyantoro, 1995). Apabila dalam karya fiksi terdapat peristiwa yang menyimpang dari pokok masalah yang dikembangkan atau menjadi bagian yang menyimpang yang tak langsung bertalian dengan alur dan tema karya sastra, bagian itu disebut sebagai digresi atau lanturan (Sudjiman, 1986). Misalnya adegan Limbukan, Cantrikan, dan Gara-gara dalam plot wayang purwa, ditinjau dari struktur isi pembicaraannyanya sebenarnya sering merupakan digresi. Namun demikian adegan tersebut sah bila ditinjau dari segi konvensi atau tradisi wayang purwa. b) Penokohan Istilah penokohan dalam ilmu sastra sering juga disebut tokoh, watak, perwatakan, karakter, atau karakterisasi. Penokohan adalah penciptaan citra tokoh di dalam karya sastra (Sudjiman, 1986). Penokohan lebih luas pengertiannya dari pada istilah tokoh dan istilah perwatakan, sebab sekaligis mencakup masalah siapa tokoh cerita, bagaimana perwatakannya, bagaimana penempatannya dan pelukisannya dalam sebuah cerita sehingga sanggup memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca. Penokohan sekaligus 81 menyaran pada teknik pewujudan dan pengembangan tokoh dalam cerita (Nurgiyantoro, 1995). Penokohan dapat digambarkan secara fisik, psikologis maupun psikologis. Dari segi fisik, misalnya: kelaminnya, tampangnya, rambutnya, bibirnya, warna kulitnya, tingginya, gemuk atau kurusnya, dsb. Dari segi psikologis, misalnya: pandangan hidupnya, cita-citanya, keyakinannya, ambisinya, sifat-sifatnya, inteligensinya, bakatnya, emosinya, dsb Dari segi sosiologis, misalnya: pendidikannya, pangkat dan jabatannya, kebangsaannya, agamanya, lingkungan keluarganya, dsb. Walaupun tokoh dan penokohannya dalam cerita itu hanya merupakan ciptaan pengarang, namun harus diperhitungkan logika kewajarannya. Ia harus merupakan tokoh yang hidup secara wajar sebagaimana kehidupan manusia yang mempunyai pikiran dan perasaan; sekaligus harus sesuai dengan tuntutan cerita dengan perwatakan yang disandangnya. Jika terjadi seorang tokoh bersikap lain, maka harus tidak terjadi begitu saja, karena harus memiliki kadar plausibilitas dan yang terpenting haruslah konsisten (bdk: Nurgiyantoro, 1995: 167). c) Latar atau Setting Latar atau setting atau landas tumpu menyaran pada tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan (Abrams, via Nurgiyantoro, 1995). Latar memberikan pijakan cerita secara konkrit dan jelas, untuk menciptakan suasana tertentu yang seolah-olah sungguh ada dan terjadi. Latar, setidak-tidaknya dapat dipisahkan menjadi latar tempat (di mana lokasinya), latar waktu (kapan terjadinya), dan latar suasana (bagaimana keadaannya); termasuk suasana alam, suasana masyarakat (sosial), dan suasana lahir dan batin tokoh cerita. Dalam karya fiksi, latar waktu yang diceritakan sering menunjuk pada waktu-waktu tertentu yang pernah berlangsung, bahkan hingga disebutkan bulan atau tahunnya, atau penunjukan pada suatu peristiwa yang pernah terjadi dalam fakta sejarah. Dengan demikian latar waktu itu seakan-akan merupakan latar yang ada dalam realita kehidupan sesungguhnya (bukan sekedar karangan). Namun demikian di dalam karya fiksi, sering dimunculkan berbagai hal yang ada pada realita kehidupan sesungguhnya, yang menurut waktunya tidak sesuai atau 82 tidak tepat sehingga fiksi tersebut menjadi tidak logis. Misalnya, pada cerita ketoprak yang mengangkat cerita historis, misalnya jaman Majapahit, lalu tokoh abdinya membicarakan tentang keluarga berencana (KB) yang sesungguhnya baru muncul pada tahun 1970-an. Hal yang menjadikan latar waktunya menjadi tidak logis itu sering disebut anakronisme (Nurgiyantoro, 1995), yakni ketidak sesuaian antara waktu dalam cerita dengan waktu dalam realita yang diacu oleh karya fiksi yang bersangkutan. 3) Sarana Sastra Sarana sastra atau sarana pengucapan sastra atau sarana kesastraan (literary devices) adalah teknik yang dipergunakan pengarang untuk memilih dan menyusun detil-detil cerita (peristiwa dan kejadian) menjadi pola yang bermakna. Tujuan penggunaan atau pemilihan sarana sastra adalah untuk memungkinkan pembaca melihat fakta sebagaimana yang dilihat pengarang, menafsirkan makna fakta sebagaimana yang ditafsirkan pengarang, dan merasakan pengalaman seperti yang dirasakan pengarang. Macam sarana sastra antara lain berupa sudut pandang penceritaan, gaya (bahasa) dan nada, simbolisme dan ironi (Nurgiyantoro, 1995). Di bawah ini terutama hanya akan dibicarakan perihal sudut pandang penceritaan dan simbolisme a) Sudut Pandang Sudut pandang atau point of view atau viewpoint, adalah cara sebuah cerita dikisahkan. Ia merupakan cara dan atau pandangan yang dipergunakan oleh pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi kepada pembaca (Abrams, via Nurgiyantoro, 1995). Jadi ia merupakan cara atau siasat atau strategi dari pengarang untuk menyampaikan ceritanya. Dalam hal ini cara yang dipakai adalah dengan mengambil posisi atau mendudukkan dirinya pada peristiwa atau cerita yang disampaikannya. Pencerita itu bisa berposisi sebagai orang luar atau orang yang tidak terlibat dalam peristiwa (-peristiwa) yang diceritakan, namun juga bisa sebagai 83 orang yang ikut terlibat dalam kejadian(-kejadian) yang diceritakan. Bila ia berada di luar kejadian-kejadian dalam cerita atau tidak terlibat, maka tokohtokoh yang diceritakan akan dipandang sebagai orang ketiga atau disebut gaya “dia” atau gaya orang ketiga. Sedang bila pencerita itu terlibat, maka ia akan menceritakan melalui tokoh “aku” atau disebut gaya “aku” atau gaya orang pertama. Penggunaan gaya orang ketiga atau pun gaya orang pertama tampak bukan pada bentuk dialog tetapi pada bentuk narasi. Dalam karya sastra Jawa gaya orang ketiga tampak pada narasi yang diungkapkan dengan kata ganti orang ketiga: dheweke atau dheke, dsb. Sedang gaya aku tampak pada narasi yang diungkapkan dengan kata ganti aku atau kula. Pada sudut pandang orang ketiga, dapat diklasifikasikan lagi menjadi: gaya “dia” maha tahu dan gaya “dia” terbatas atau tidak maha tahu. Bila berbagai hal yang dialami tokoh (-tokoh) cerita, termasuk apa pun yang dipikirkan atau dirasakan atau dipendam dalam hati, diketahui oleh pencerita sehingga diceritakan dalam suatu fiksi, maka sudut pandang itu termasuk gaya “dia” maha tahu. Namun bila pencerita tidak menceritakan hal-hal yang ada dalam pikiran atau batin tokoh- tokoh cerita, maka termasuk dalam gaya “dia” terbatas. Gaya “dia” terbatas…….pengamat. b. Simbolisme SIMBOLISME 2. Sastra Puisi Jawa Modern Ditinjau dari bentuknya, puisi Jawa modern dapat dibagi menjadi dua golongan, yakni: (1) puisi Jawa tradisional dengan bentuk yang mematuhi berbagai aturan konvensional yang telah ada secara turun temurun, dan (2) puisi Jawa modern atau geguritan modern dengan bentuk yang kurang atau tidak harus mematuhi berbagai aturan konvensional. Pada puisi Jawa tradisional, masih dapat dibagi lagi menjadi sebagai berikut. (a) Puisi yang memiliki aturan-aturan yang ketat dan relatif kompleks. Aturan yang dimaksud adalah aturan tentang lampah pada tembang 84 gedhe atau aturan yang menyangkut guru lagu, guru wilangan dan guru gatra pada tembang tengahan dan macapat. Puisi ini yang kemudian disebut tembang yasan atau tembang miji. (b) Puisi yang mempunyai aturan sederhana, tidak sampai pada aturanaturan yang ketat, baik aturan tentang lampah atau tentang guru lagu, guru wilangan dan guru gatra. Puisi ini yang kemudian dikenal dengan nama tembang para. a) Tembang Yasan atau Tembang Miji Dalam jenis tembang yasan, terdapat pola metris yang ditentukan oleh beberapa hal, baik yang menyangkut patokan lampah atau tiga patokan pokok, yakni guru lagu, guru wilangan dan guru gatra, (yang telah diuraikan di bagian depan ketika membicarakan tentang kidung). Sebenarnya di samping patokan-patokan di atas, tembang yasan akan menjadi lebih baik bila juga memperhatikan aturan-aturan yang lain, yakni sebagai berikut. 1). Makna tiap baitnya sebaiknya telah bulat, satu kesatuan makna tertentu tidak terputus dan dimasukkan ke dalam bait berikutnya. 2). Jeda kalimat pada setiap baitnya (andhegan) hendaknya sesuai dengan jeda yang ada pada jenis lagu tembang yang bersangkutan. Jeda ini biasanya antara dua dan tiga baris. 3). Setiap baris hendaknya merupakan kalimat lengkap atau bagian kalimat yang dapat berdiri sendiri. 4). Penggalan baris (pedhotan) hendaknya jatuh pada akhir kata sehingga menghasilkan wirama kendho. Bila pedhotan-nya bukan akhir kata disebut wirama kenceng. 5). Sebaiknya memperhatikan persajakan, baik asonansi (purwakanthi swara) maupun aliterasi (purwakanthi sastra); atau purwakanthi lumaksita (suku kata atau kata terakhir bersajak dengan atau diulang pada kata atau suku kata awal pada bagian di belakangnya), baik sajak horizontal maupun vertikal. 6). Sebaiknya memperhatikan tradisi penulisan yang ada, seperti cara penulisan nama samaran pengarang (sandi asma), cara penulisan waktu (sengkalan), 85 tradisi penulisan sasmitaning tembang, cara penulisan wangsalan dan sebagainya, yang sering disisipkan dalam bentuk tembang yasan (Bdk. Padmopuspito, 1989: 85). Sebagai contoh di bawah ini jenis tembang macapat Dhandhanggula. Song-song gora / candraning hartati / lir winidyan / sarosing parasdya / ringa-ringa / pangriptane // tan darbe / labdeng kawruh / angruruhi / wenganing budi // kang mirong / ruhareng tyas / njaga / angkara nung // minta luwar / ring duhkita / aywa kongsi / kewran lukiteng kinteki / kang kata / ginupita // (Serat Cemporet karya R.Ng. Ranggawarsita) Tembang Dhandhanggula adalah salah satu jenis tembang yasan yang termasuk dalam jenis tembang macapat, yang dapat diuraikan sebagai berikut. Garis-garis ( / ) di tengah baris atau di akhir baris pada tembang Dhandhanggula di atas merupakan pedhotan. Adapun garis-garis ( // ) pada beberapa akhir barisnya merupakan andhegan. Pedhotan dan andhegan merupakan hasil pola metris dalam hubungannya dengan cengkok atau cara menembangkannya. Guru gatra Dhandhanggula seperti di atas adalah 10 baris. Guru wilangan dan guru lagu-nya adalah: 10:i , 10:a , 8: e, 7:u, 9:i, 7:a, 6:u, 8:a, 12:i, 7:a. Satu bait tersebut telah mengandung satu pengertian (makna) yang bulat. Andhegan-nya berada pada 3 baris, 2 baris, 2 baris , dan 3 baris. Tiap baris merupakan bagian kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Semua pedotannya merupakan pedhotan kendho. Persajakannya, yang berupa purwakanthi sastra dapat diperhatikan pada kata gora dengan candra, kata raosing dengan parasdya, kata ringa-ringa dengan pangriptane, kata darbe dengan lebdeng, dsb. Dalam contoh di atas, pada suku kata-suku kata yang digarisbawahi merupakan sandi asma yang berbunyi radyan ngabehi ronggawarsita (R.Ng. Ranggawarsita) 86 (mengenai sandi asma, di atas sudah dijelaskan). Sedang pada rangkaian kata song song gora candra adalah bentuk sengkalan: Song = 9, song = 9, gora = 7, dan candra = 1, jadi tahun 1799 AJ (mengenai sengkalan akan di jelaskan di bawah). Berdasarkan pada bentuk pola metrisnya, tembang yasan dibagi menjadi tiga, yakni tembang gedhe, Tembang Tengahan dan Tembang Macapat. 1) Tembang gedhe Tembang gedhe adalah tembang yasan yang aturannya terkait dengan konvensi lampah, yakni kesamaan jumlah suku kata dalam setiap baris. Adapun jumlah baris dalam semua tembang gedhe adalah sama, yakni selalu 4 (empat) baris. Sedang aturan tentang guru lagu (dhong-dhing) tidak ada dalam tembang gedhe ini. Nama-nama tembang gedhe ditengarai oleh aturan lampah tembang yang bersangkutan, yakni antara lampah 1 (setiap baris terdiri satu suku kata) hingga lampah 28 (ada yang berpendapat hingga lampah 32) (Subalidinata, tt: 37, Padmopuspito, 1989: 87). Bila bertolak dari puisi Jawa Kuna yang disebut kakawin, aturan yang berlaku dalam tembang gedhe ini hampir sama dengan kakawin. Bedanya, dalam tembang gedhe tidak terdapat aturan tentang suku kata panjang dan suku kata pendek seperti dalam kakawin. Nama-nama metrum tembang gedhe dengan lampah dan pedhotan (penggalannya) sebagai berikut (Padmopuspito, 1989: 87-88). Lam Metrum Pedhotan Lam pah Metrum Pedhotan pah 1 Nanda - 15 Manggalagita 8,7 2 Badra Sri Waneh - 15 Musthikengrat 8,7 3 Nari - 15 Langenkusuma 7,8 4 Wanamergi - 15 Kumudasmara 7,8 5 Wijayanti 2,3 15 Pamularsih 7,8 5 Giyanti 3,2 16 Rarabentrok 8,8 87 5 Rerantang 1,4 16 Rara Turida 8,8 5 Puksara 3,2 16 Candrakusuma 8,8 6 Tanumadya 2,4 16 Candraasmara 8,8 6 Gurnang 2,4 16 Sebamanggala 8,8 6 Liwung 2,4 17 Ciptamaya 5,5,7 6 Binayaa 4,2 17 Bangsapatra 4,6,7 7 Madukaralalita 3,4 17 Sikarini 6,6,5 7 Sundari 3,4 17 Puspamadya 6,6,5 8 Waktra 4,4 17 Priyambada 6,6,5 8 Salisir 4,4 18 Nagabanda 5,6,7 8 Patramanggala 4,4 18 Narakusuma 5,6,7 8 Patralalita 4,4 18 Langendikara 5,6,7 8 Wipula 4,4 18 Nagakusuma 6,6,6 8 Kuswaraga 4,4 19 Sardulawikridita 6,6,7 9 Jaraga Tata Gati 4,5 19 Banjaransari 6,6,7 9 Tebu Kasol 4,5 19 Pritanjala 6,6,7 9 Mayanti 4,5 19 Dhudhagandrung 4,5,5,5 10 Rukmawati 4,6 20 Sasadara Kawekas 7,7,6 10 Rukmarata 4,6 20 Swandana 7,7,6 10 Tebusauyun 5,5 20 Sulanjari 4,4,4, 8 11 Bremarawilasita 4,7 20 Angron Asmara 8,6,6 11 Lebdajiwa 4,7 21 Wisalyaharini 7,7,7 12 Jiwawicitra 6,6 21 Swaladara 7,7,7 12 Jiwaretna 6,6 22 Irim-irim 8,7,7 12 Kusumawicitra 6,6 22 Kilayunedheng 5,6,6,5 12 Sudirawicitra 5,7 23 Haswalalita 5,6,6,6 12 Padmawicitra 4,4,4 23 Purbanagara 5,6,6,6 12 Citrakusuma 6,6 23 Hastakuswala 6,6,5,6 12 Citramengeng 6,6 23 Kanigara 8,8,7 12 Citrarini 5,7 24 Gandakusuma 6,6,6,6 88 12 Prawirasembada 5,7 24 Wohingrat 6,6,6,6 13 Dhadhapsari 5,8 24 Gandasuli 6,6,6,6 13 Madubrangta 5,8 24 Jayaningrat 6,6,6,6 13 Pusparaga 7,6 24 Jayengtilam 6,6,6,6 13 Puspanjali 7,6 25 Kudukusuma 4,4,5,6,6 13 Kusumastuti 7,6 25 Kusumatali 4,4,5,6,6 14 Rarasmara 6,8 26 Kumudaningrat 6,7,7,7 14 Langenasmara 6,8 27 Langenjiwa 6,6,7,8 14 Pusparudita 7,7 28 Pramugari 7,7,7,7 14 Sorohjiwa 7,7 14 Basanta 8,6 Di samping nama-nama di atas, masih dimungkinkan nama-nama metrum yang lain. Nama metrum tembang gedhe biasanya dicantumkan dalam akhir bait tertentu. Sebagai contoh tembang Rerantang lampah 5 di bawah ini. Dhuh babo sira ywa walang driya nedya bawa ing tembang Rerantang Contoh lain bernama metrum Puspanjana, sebagai berikut. Dhuh Gusti pujaningwang sotyaning wanita myang maduning kusuma sekaring bawana tuhu mustikaning rat dadya sudarsana sagunging pra wanodya ambek Puspanjana (R. Tedjohadisumarto, 1958: 26 ) Satu contoh lagi bernama Kusumawicitra, sebagai berikut. Pirang-pirang taunira neng patapan malah kongsi diwasa aneng patapan ing Gohkarna wukir ageng dahat pringga tan etang durgameng kusumawicitra (Arjunasasra: II.16, Subalidinata, tt: 37- 40) 89 2) Tembang Tengahan Tembang tengahan sering juga disebut tembang dhagel atau tembang tanggung atau tembang madya. Tembang tengahan terikat oleh tiga patokan dasar, yakni guru gatra, guru wilangan dan guru lagu, yakni yang telah diuraikan di atas. Dalam khasanah sastra Jawa Kuna (Jawa Tengahan) jenis puisi yang terikat oleh aturan seperti ini disebut kidung (baca bagian tentang kidung!). Adapun nama-nama tembang tengahan dan aturannya, sebagai berikut (bdk. Subalidinata, tt: 43, Padmopuspito, 1989: 88-89, dan Padmosoekotjo, tt, jld I: 22). Nama Metrum Guru Gatra Guru Wilangan Guru lagu Lonthang 3 12,12,12 a,a,a Balabak 6 12,3,12,3,12,3 a,e,a,e,a,e Girisa 8 8,8,8,8,8,8,8,8 a,a,a,a,a,a,a,a Wirangrong 6 8,8,10,6,7,8 i,o,u,i,a,a Jurudemung 7 8,8,8,8,8,8,8 a,u,u,a,u,a,u Palugon 8 8,8,8,8,8,8,8,8 a,u,o,u,o,a,u,o Pranasmara 6 8,12,12,8,8,8 a,e,e,a,a,i Pangajapsih 9 12,8,12,12,12,8,8,6,8 u,i,u,u,u,a,i,u,a Kuswarini 7 12, 6,8,8,8,8,8 u,a,u,a,i,a,i Dalam hal kategori tembang tengahan atau tembang macapat, beberapa pakar tampak berbeda-beda pengelompokannya. Beberapa metrum tembang tengahan di atas oleh pakar lain kadang-kadang diklasifikasikan sebagai tembang macapat. Dengan demikian agaknya dapat dimengerti pernyataan Poerbatjaraka, bahwa pada dasarnya tembang tengahan itu tidak ada dan yang dimaksud tembang tengahan adalah tembang macapat yang usianya tua dan hampir dilupakan. 90 3) Tembang Macapat Telah disinggung di atas bahwa seperti halnya tembang tengahan, tembang macapat terikat oleh tiga aturan pokok, yakni guru lagu, guru wilangan dan guru gatra, yakni suatu aturan yang juga sudah ada pada bentuk kidung berbahasa Jawa Tengahan. Tidak mengherankan bila metrum Pamijil dalam kidung sama dengan metrum Mijil dalam tembang macapat. Tembang macapat juga disebut sekar alit. Di bawah ini sejumlah nama tembang macapat dengan guru gatra, guru wilangan dan guru lagu-nya. Metrum Guru Guru Wilangan Guru lagu Gatra Pucung 4 12,6,8,12 u,a,i,a Maskumambang 4 12,6,8,8 i,a,i,a Megatruh 5 12,8,8,8,8 u,i,u,i,o Gambuh 5 7,10,12,8,8 u,u,i,u,o Mijil 6 10,6,10,10,6,6 i,o,e,i,i,u Kinanthi 6 8,8,8,8,8,8 u,i,a,i,a,i Pangkur 7 8,11,8,7,12,8,8 a,i,u,a,u,a,i Durma 7 12,7,6,7,8,5,7 a,i,a,a,i,a,i Asmaradana 7 8,8,8,8,7,8,8 i,a,e ( o),a,a,u,a Sinom 9 8,8,8,8,7,8,7,8,12 a,i,a,i,i,u,a,i,a Dhandhanggula 10 10,10,8,7,9,7,6,8,12,7 i,a,e,u,i,a,u,a,i,a Di bawah ini contoh tembang Pucung dan tembang Asmaradana. Pucung. Ngelmu iku kelakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangekese dur angkara (Wedhatama III: 1, karya K.G.P.A.A Mangkunagara IV) Asmaradana 91 Anjasmara ari mami mas mirah kulaka warta dasihmu tan wurung layon aneng kutha Prabalingga prang tandhing Urubisma kariya mukti wong ayu pun kakang pamit palastra (dari: Serat Patine Menakjingga) 4) Sasmitaning Tembang Dalam jenis tembang macapat, sering terdapat isyarat tentang nama metrum tembang pada pupuh yang bersangkutan atau metrum tembang pada pupuh selanjutnya. Isyarat tembang tersebut lazim disebut sasmitaning tembang. Sasmitaning tembang biasanya berupa kata, frasa, atau baris tertentu yang mempunyai makna yang bersinggungan dengan nama tembang yang diisyaratkan. Sebagai contoh frasa yuda kenaka sering dipergunakan untuk sasmitaning tembang Pangkur. Kata yuda berarti ‘perang’ atau ‘bertengkar’, sedang kata kenaka berarti ‘kuku’. Jadi kata yuda kenaka bisa bermakna ‘berperangnya kuku’ atau menggaruk atau dalam bahasa Jawa kukur-kukur. Kata kukur-kukur bersinggungan dengan nama tembang Pangkur, yakni pada suku kata kur. Sasmitaning tembang macapat sering terdapat pada bait yang mengawali pupuh tembang yang bersangkutan atau pada bait terakhir sebelum pergantian pupuh untuk memberi isyarat nama metrum tembang yang akan menggantikan pupuh yang bersangkutan. Kata-kata tertentu yang sering dipergunakan sebagai sasmitaning tembang pada umumnya bersinggungan dengan nama metrum tembangnya. Kebersinggungannya pada umumnya sebagai berikut. a) Bisa dalam hal kesamaan bunyi salah satu suku katanya. Sebagai contoh untuk tembang Sinom dipergunakan kata anom (kesamaan suku kata nom), untuk Pangkur dipergunakan kata mingkar-mingkur (kesamaan suku kata kur), dsb. 92 b) Bisa dalam sinonim arti katanya. Contohnya, untuk tembang Sinom dipergunakan frasa roning kamal. Kata roning kamal berarti ‘daun pohon asem’. Daun pohon asem pada umumnya disebut daun sinom, dsb. c) Bisa sifat-sifat tertentu pada kata atau frasa yang ada dalam nama metrumnya. Sebagai contoh untuk tembang Dhandhanggula dipergunakan kata manis. Manis adalah sifat rasa gula. Sasmitaning tembang selengkapnya sebagai berikut. Untuk tembang Dhandhanggula antara lain dipergunakan kata, frasa, atau larik: dhandhanggula, manis, madu manis, kaga kresna, gagak, hartati, sarkara, guladrawa, dhandhang, dhandhanggendhis, akudhandhangan, andhandhang sarkara, didhandhang, ndhandhanggula, dsb. Untuk tembang Sinom antara lain dipergunakan kata atau frasa: sinom, sesinoming, tumaruna, srinata, roning kamal, logondhang, sinom, anom, Anoman, taruna, taruni, weni, mudha, dsb. Untuk tembang Pangkur antara lain dipergunakan kata atau frasa: pangkur, pungkur, kapungkur, mingkar-mingkur, kukur-kukur, yuda kenaka, wuntat, wuri, mungkur, sapengkernya, wingking, dsb. Untuk tembang Asmaradana antara lain dipergunakan kata atau frasa: asmaradana, asmara, kasmaran, nawung brangti, rarasing kingkin, kasmaran, branta, rarasing ati, satyasmara, brangta kingkin, dsb. Untuk tembang Durma antara lain dipergunakan kata atau frasa: durma, mundur, undurana, kunduran, kondur, kadurmaning, dsb. Untuk tembang Mijil antara lain dipergunakan kata atau frasa: mijil, wijiling, wuryaning, miyos, kawiyos, kawijil, metu, medal, dsb. Untuk tembang Kinanthi antara lain dipergunakan kata atau frasa: kinanthi, kanthi, kanthining, gegandhengan, anganthi, kanthinira, dsb. Untuk tembang Maskumambang antara lain dipergunakan kata atau frasa: maskumambang, kumambang, kambang-kambang, tumimbul ing toya, timbul ing warih, mas kinambang, mas kentir, kentar, ngemasi, dsb. Untuk tembang Pucung antara lain dipergunakan kata atau frasa: pucung, pinucung, acung, pamucunging, dsb. 93 Untuk tembang Gambuh antara lain dipergunakan kata atau frasa: gambuh, tambuh, wimbuh, gegambuhan, dsb. Untuk tembang Megatruh (Dudukwuluh) antara lain dipergunakan kata atau frasa: megatruh, megat, truh, anduduk, duduk wuluhe, dsb. Sebagai contoh, sasmitaning tembang yang ada pada bait di awal pupuh, yakni pada pupuh Pangkur, sebagai berikut. Mingkar-mingkuring angkara / akarana karenan mardi siwi / sinawung resmining kidung / sinuba sinukarta / mrih kretarta pakartining ngelmu luhung / kang tumrap neng tanah Jawa / agama ageming aji // Adapun contoh sasmitaning tembang yang terdapat pada akhir bait di dalam pupuh sebelumnya adalah sebagai berikut. Surya candra langit lawan bumi / mega banyu angin sadayanya / pinamitan samuhane / saestua tumulus / waluya ring ayu lestari / prayitna saking mula / mula purwanipun / anunggal karsaning titah / ala ayu wus tinitah batharadi / liring yudakanaka // Pada contoh terakhir ini, semula berupa pupuh Dhandhanggula, jadi tembang tersebut berupa tembang Dhandhanggula, kemudian tentu saja akan berganti pupuh Pangkur, karena di situ sudah didahului dengan isyarat atau sasmitaning tembang berbunyi yudakenaka. Dalam tiga jenis tembang yasan di atas (tembang gedhe, tembang tengahan dan tembang macapat), sering terdapat istilah yang disebut pupuh, seperti telah disebut-sebut di atas. Pupuh adalah suatu kesatuan yang terdiri atas satu bait atau lebih yang sama metrumnya. Dalam bahasa Belanda pupuh disebut zang, sedang dalam bahasa Inggris disebut canto. Dalam satu judul karya sastra Jawa yang berbentuk tembang, bisa terdiri atas satu pupuh saja (misalnya pupuh Dhandhanggula saja atau Pangkur saja, dsb), tetapi juga bisa lebih dari satu pupuh (misalnya pupuh Pangkur, pupuh Mijil, pupuh Asmaradana, dsb). 5) Karakter atau Wataking Tembang Dalam tembang yasan, terutama tembang macapat dan tembang tengahan, pernah dilontarkan suatu teori bahwa setiap jenis tembang mempunyai wataknya masing-masing. Padmosoekatjo (tt, jld. I: 22-23) misalnya, menyatakan 94 bahwa penggunaan tembang semestinya mengingat waktak tembang masingmasing, yakni sbb. 1. Kinanthi, berwatak senang, kasih, cinta. Tepatnya dipergunakan untuk menbeberkan ajaran, cerita yang berisi cinta kasih , asmara, atau jatuh cinta (gandrung) 2. Pucung, berwatak santai (kendho), tanpa ambisi, seenaknya. Tepatnya untuk menceritakan sesuatu yang netral, tanpa ambisi tertentu. 3. Asmaradana, berwatak jatuh cinta, sedih, prihatin. Dalam hal ini sedih dan prihatin yang disebabkan oleh perasaan jatuh cinta. Tepatnya untuk menceritakan tentang jatuh cinta. 4. Mijil, berwatak ekspresif (wedharing rasa). Tepatnya untuk mengekspresikan ajaran tertentu, namun juga dapat untuk mengungkapkan perasaan jatuh cinta. 5. Maskumambang, berwatak kesal, sedih, menyesal. Tepatnya untuk mengungkapkan perasaan sakit hati, sedih, kesal, menyesal. 6. Pangkur, berwatak keras, marah. Tepatnya untuk mengungkapkan perasaan marah, geregetan, ekspresi keras. Jika untuk mengungkapkan ajaran tertentu, yakni ajaran yang bernada marah. Bila untuk mengungkapkan perasaan cinta, cinta yang sangat bergejolak. Pada umumnya juga untuk menceritakan perang. 7. Sinom, berwatak ramah, segar. Cocoknya untuk mengungkapkan ajaran atau pendidikan. 8. Dhandhanggula, berwatak luwes, senang. Dapat untuk berbagai macam cerita, antara lain untuk membuka atau menutup cerita, untuk mengajar, untuk cerita perihal jatuh cinta, dsb. 9. Durma, berwatak keras (galak), marah (muntab). Tepatnya untuk mengungkapkan kemarahan, luapan dendam, atau cerita perang. 10. Gambuh, berwatak ramah, sehati, terbiasa, kenal akrab. Cocok untuk mengungkapkan ajaran yang agak keras karena sudah akrab, sehingga penyampaian ajarannya dapat dengan bahasa ragam ngoko, suatu ragam bahasa bagi mereka yang telah akrab. 95 11. Megatruh, berwatak sedih, prihatin, atau putus asa. Tepatnya untuk mengungkapkan perasaan sedih, menyesal tiada henti, atau putus asa. 12. Balabak, berwatak nakal, senda gurau, tidak serius. Tepatnya untuk mengungkapkan cerita yang tidak serius atau senda gurau. 13. Wirangrong, berwatak berwibawa, agung. Tepatnya untuk mengungkapkan perasaan ketertarikan pada budi baik, ajaran luhur, dsb. 14. Jurudemung, berwatak lincah menyenangkan, indah. Tepatnya untuk mengungkapkan tentang hal-hal yang indah menyenangkan atau menarik hati. 15. Girisa, berwatak mengharapkan atau memesan. Tepatnya untuk mengungkapkan ajaran yang memesan atau mengharapkan sesuatu kepada orang lain. Walaupun banyak pujangga dan pengarang yang menguasai teori perwatakan tembang tersebut, namun pada realitanya, tidak setiap karya sastra yang berbentuk tembang setia memperhatikan dan mengikuti pola perwatakan tembang tersebut. Hal ini antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. 1. Bait-bait tembang yang tergabung menjadi satu dan disebut pupuh, sering kali tidak dapat luwes untuk selalu mengikuti perkembangan latar cerita atau suasana batin cerita. Dalam satu pupuh sering berisi cerita yang berlatar suasana yang bermacam-macam secara bergantiganti. Dapat saja hanya dalam beberapa bait saja, latar suasana dalam cerita telah berganti, sementara pupuh-nya belum berganti. 2. Hal di atas bermula pada unit atau kesatuan bait (pada) tembang. Sering kali pergantian latar suasana terjadi di antara baris-baris tembang yang ada dalam suatu bait tembang tertentu. Dengan demikian tidak mungkin kesatuan bait tersebut dipenggal dalam barisbaris yang belum selesai menurut aturan guru gatra-nya. Hal ini jelas berbeda sekali bila dibandingkan dengan jenis puisi bebas, apalagi dengan jenis prosa. Puisi Jawa modern yang disebut geguritan, baitbaitnya tidak terikat oleh jumlah barisnya, bahkan sering kali hanya terdiri atas satu baris dengan satu atau dua kata saja. Dengan demikian 96 pergantian suasana kejiwaannya lebih bebas, dapat berganti-ganti setiap saat. Jauh lebih bebas lagi pada jenis prosa yang dapat mendeskripsikan secara detail perkembangan suasana kejiwaan pada cerita yang disuguhkan. Bila dicermati lebih jauh, agaknya teori tentang watak tembang menurut jenis tembang-nya tersebut perlu ditinjau kembali, mengingat adanya berbagai cengkok atau lagu pada setiap jenis tembang. Kiranya akan lebih tepat bila watak tembang itu ditinjau dari jenis cengkok-nya, karena setiap cengkok tembang membawakan rasa alunan lagunya masing-masing yang tentu saja juga menyuguhkan sifat atau wataknya masing-masing yang berbeda-beda. 6) Jenis-jenis Cengkok Lagu Macapat Yang dimaksud cengkok adalah jenis gaya atau tipe lagu tertentu pada tembang yang disesuaikan dengan nada dan irama iringan gamelan. Tembang, pada dasarnya merupakan sastra lisan, disebarkan dari mulut ke mulut dengan cara dilagukan (ditembangkan). Secara umum diketahui bahwa setiap nada dan irama itu mengandung rasa masing-masing yang juga bisa dikatakan sebagai sifat atau watak nada dan irama yang bersangkutan. Tentu saja hal ini juga berlaku pada setiap cengkok lagu tembang macapat. Namun sayang sekali sampai saat ini belum ditemukan teori yang mengidentifikasikan masing-masing watak cengkok lagu tembang. Adapun jenis-jenis cengkok lagu tembang macapat adalah sebagai berikut (Prawiradisastra, 1993: 88-91). (1). Pucung (a) Pucung Tunjungseta Slendro pathet sanga (b) Pucung Dengklung Slendro pathet manyura (c) Pucung Gliyung Pelog pathet nem (d) Pucung Larasmadya Pelog pathet barang (e) Pucung Paseban Slendro pathet sanga (f) Pucung Sangubranta Pelog pathet bem (g) Pucung Randhasemaya Pelog pathet barang (h) Pucung Klenthung Slendro pathet sanga (i) Pucung Linduran Slendro pathet sanga 97 (2) Maskumambang (a) Maskumambang Buminata Slendro pathet sanga (b) Maskumambang Kembangtiba Pelog pathet nem (c) Maskumambang Dhadhapan Pelog pathet nem (d) Maskumambang Limaran Pelog pathet nem (e) Maskumambang Malatsih Pelog pathet nem (f) Maskumambang Rencasih Pelog pathet nem (g) Maskumambang Mangkubumen Pelog pathet barang (h) Maskumambang Natakusuman Peog pathet barang (3) Gambuh (a) Gambuh Panglipur Slendro pathet sanga (b) Gambuh Tejamaya Slendro pathet sanga (c) Gambuh Buminatan Slendro pathet manyura (d) Ganbuh Wewarah Pelog pathet barang (e) Gambuh Lala Pelog pathet nem (f) Gambuh Natakusuman Pelog pathet nem (g) Gambuh Mangkubumen Pelog pathet nem (h) Gambuh Genjung Pelog pathet nem (i) Gambuh Gonjing Pelog pathet nem (j) Gambuh Rimang Pelog pathet nem (4) Megatruh (a) Megatruh Wulugadhing Slendro pathet manyura (b) Megatruh Ngurawan Slendro pathet sanga (c) Megatruh Sastranagaran Pelog pathet barang (d) Megatruh Gagatan Pelog pathet barang (e) Megatruh Tejamaya Pelog pathet nem (f) Megatruh Kocak Pelog pathet nem (g) Megatruh Amonglulut Pelog pathet nem (h) Megatruh Tunjungseta Pelog pathet nem 98 (5) Wirangrong (a) Wirangrong Tunjungseta Slendro pathet sanga (b) Wirangrong Tejamaya Slendro pathet sanga (c) Wirangrong Natakusuman Slendro pathet sanga (d) Wirangrong Lagu Maos Pelog pathet bem (e) Wirangrong Buminatan Pelog pathet nem (f) Wirangrong Mangkubumen Pelog pathet nem (g) Wirangrong Wiratmaya Pelog pathet nem (6) Balabak (a) Balabak Patranala Slendro pathet sanga (b) Balabak Marasanja Slendro pathet sanga (c) Balabak Lara-lara Slendro pathet sanga (d) Balabak Tinjomaya Pelog pathet nem (e) Balabak Tunjungseta Pelog pathet barang (f) Balabak Wirabangsa Pelog pathet barang (3) Kinanthi (a) Kinanthi Mangu Slendro pathet manyura (b) Kinanthi Sekargadhung Slendro pathet manyura (c) Kinanthi Sandhung Slendro pathet manyura (d) Kinanthi Gagatan Slendro pathet sanga (e) Kinanthi Kasilir Pelog pathet bem (f) Kinanthi Panglipurwuyung Pelog pathet nem (g) Kinanthi Pujamantra Slendro pathet sanga (h) dsb. (4) Mijil (a) Mijil Sekarsih Slendro pathet manyura (b) Mijil Larasati Slendro pathet sanga (c) Mijil Tinjomaya Slendro pathet sanga 99 (d) Mijil Wedharingtyas Pelog pathet bem (e) Mijil Raramanglong Pelog pathet nem (f) Mijil Larasdriya Pelog pathet barang (g) Mijil Kulanthe Pelog pathet barang (5) Asmaradana (a) Asmaradana Kadhaton Slendro pathet sanga (b) Asmaradana Tinjomaya Slendro pathet sanga (c) Asmaradana Mangkubumen Slendro pathet sanga (d) Asmaradana Lagu Kawin Pelog pathet bem (e) Asmaradana Lagu Slobog Pelog pathet barang (f) Asmaradana Bawaraga Pelog pathet barang (g) Asmaradana Semarangan Pelog pathet nem (h) Asmaradana Jakalola Pelog pathet nem (6) Pangkur (a) Pangkur Laras Madya Slendro pathet sanga (b) Pangkur Paripurna Slendro pathet sanga (c) Pangkur Dhudhakasmaran Slendro pathet sanga (d) Pangkur Suranggagreget Slendro pathet manyura (e) Pangkur Kasmaran Pelog pathet nem (f) Pangkur Nyamatmas Pelog pathet nem (g) Pangkur Gegersore Pelog pathet nem (h) Pangkur Ngrenasmara Pelog pathet nem (7) Durma (a) Durma Dhendharangsang Slendro pathet manyura (b) Durma Rangsang Slendro pathet sanga (c) Durma Gagatan Slendro pathet sanga (d) Durma Surengkewuh Pelog pathet barang 100 (e) Durma Guntur Pelog pathet barang (f) Durma Linduran Pelog pathet barang (g) dsb. (8) Jurudemung (a) Jurudemung Lagu Maos Slendro pathet sanga (b) Jurudemung Buminatan Pelog pathet barang (c) Jurudemung Tunjungseta Slendro pathet sanga (d) Jurudemung Tunjungseta Pelog pathet nem (e) Jurudemung Natakusuman Slendro pathet sanga (f) Jurudemung Natakusuman Pelog pathet barang (g) Jurudemung Sastranegaran Slendro pathet sanga (h) Jurudemung Sastranegaran Pelog pathet barang (9) Girisa (a) Girisa Tejamaya Slendro pathet sanga (b) Girisa Ruhara Slendro pathet sanga (c) Girisa Wantah Maos Pelog pathet nem (d) Girisa Kasaya Pelog pathet nem (e) Girisa Natakusuman Pelog pathet barang (f) Girisa Buminatan Pelog pathet barang (10) Sinom (a) Sinom Wenikenya Slendro pathet sanga (b) Sinom Logondhang Slendro pathet sanga (c) Sinom Mengkreng Slendro pathet sanga (d) Sinom Pangrawit Slendro pathet manyura (e) Sinom Kentar Slendro pathet manyura (f) Sinom Ginonjing Pelog pathet nem (g) Sinom Bangwetan Pelog pathet nem (h) Sinom Wenikepyur Pelog pathet barang 101 (11) Dhandhanggula (a) Dhandhanggula pasowanan Slendro pathet sanga (b) Dhandhanggula Padhasih Slendro pathet sanga (c) Dhandhanggula Rencasih Slendro pathet manyura (d) Dhandhanggula Tlutur Slendro pathet sanga (e) Dhandhanggula Banjet Pelog pathet barang (f) Dhandhanggula Baranglaya Pelog pathet barang (g) Dhandhanggula Penganten anyar Pelog pathet nem (h) Dhandhangula Kanyut Pelog pathet nem (i) Dhandhangula Turulare Pelog pathet nem Seperti telah disinggung di atas, dalam bentuk tembang yasan, sering disisipkan bentuk-bentuk khusus, antara lain sandi asma, sengkalan, wangsalan dan sebagainya. Perihal sandi asma telah di bicarakan di atas. Sedang wangsalan akan dibahas dalam hubungannya dengan jenis tembang para. Adapun sengkalan dapat dijelaskan sebagai berikut. 7) Sengkalan Dalam bentuk tembang, khususnya macapat, selain sasmitaning tembang dan sandiasma, masih ada jenis-jenis tertentu yang juga sering diselipkan di antara baris-baris atau bait-bait tembang macapat itu, yakni antara lain sengkalan. Kata sengkalan mungkin berasal dari kata saka kala dan akhiran -an, yakni hitungan waktu yang berdasarkan tahun Saka, karena pada mulanya sengkalan memang berdasarkan tahun Saka (Subalidinata, 1981: 92- 93). Namun kemudian pengucapannya bergeser menjadi sangkalan yang dapat juga berasal dari kata sang kala dan akhiran -an. Kata kala dalam bahasa Jawa baru dapat berarti ‘waktu’, sedang akhiran -an dapat bermakna ‘membentuk kata benda baru’ atau bermakna ‘tempat’. Jadi sengkalan dimaknai sebagai ‘tempat atau bagian yang menandakan waktu atau tahun’. 102 Sengkalan berisi gambar, atau ornamen atau relief atau semacam patung yang merupakan simbol dari rangkaian kata-kata atau rangkaian kata-kata itu sendiri yang mempunyai makna nilai bilangan dan nilai bilangannya dimaknai dari belakang sebagai angka tahun. Jadi dari segi cara ekspresinya, sengkalan ada dua macam, yakni sengkalan memet dan sengkalan lamba. Sengkalan memet ialah sengkalan yang berupa bangunan bergambar atau relief atau semacam patung. Kata memet atau njlimet berarti ‘rumit’. Disebut memet karena penafsirannya lebih rumit. Menurut Subalidinata (1981: 93), dalam bahasa Jawa, gambar atau relief sering disebut pepethan, oleh karena itu sengkalan memet juga disebut sangkala petha. Adapun sengkalan lamba ialah sengkalan yang telah berupa rangkaian kata atau kalimat. Kata lamba dapat berarti ‘sederhana’. Jadi sengkalan lamba maksudnya adalah sengkalan yang lebih sederhana (dibanding sengkalan memet). Dalam bentuk tembang, atau dalam kitab-kitab di Jawa tentu saja yang ada adalah sengkalan lamba. Sengkalan sebenarnya telah ada sejak sastra Jawa Kuna. Misalnya terdapat dalam kitab Bharatayudha karya Mpu Sedah dan Mpu Panuluh. Sengkalan yang ada berbunyi sanga kuda śuddha cāndramā, yang berarti tahun Saka 1079. Kata sanga bernilai sembilan, kata kuda bernilai tujuh, kata suddha bernilai nol, dan kata candrama bernilai satu. Contoh yang berupa sengkalan memet terdapat dalam candi Sukuh berupa relief seekor lembu menggigit ekornya, yang harus dimaknai goh wiku naut buntut atau tahun Saka 1378; dan gapuranya berujud raksasa makan orang yang harus dimaknai gapura buta mangan wong atau tahun 1379 Saka. Dari segi dasar perhitungan tahunnya, ada dua sengkalan yakni surya sengkala dan candra sengkala. Surya sengkala adalah sengkalan yang tahunnya dihitung berdasarkan tahun matahari. Adapun candra sengkala dihitung berdasarkan hitungan tahun bulan. Menurut Padmosoekotjo (tt, jld. II: 134), kata-kata yang dipergunakan dalam sengkalan adalah kata-kata yang mengandung makna watak bilangan. Kata-kata yang dipilih adalah sesuai dengan nilai atau watak angkanya, sekaligus disesuaikan dengan peristiwa atau kejadiannya. Hal ini dikarenakan tujuan 103 pembuatan sengkalan adalah untuk mengingat-ingat tahun terjadinya sesuatu. Pada dasarnya watak bilangan yang ada dalam sengkalan sebagai berikut. 1) Bernilai satu ialah kata-kata untuk bilangan satu, atau barang atau manusia atau bagian tubuh manusia atau binatang yang berjumlah satu, atau barang yang berbentuk bulat, atau bermakna ‘berani’. Kata-kata yang bernilai satu antara lain, wulan (bulan), candra (bulan), sasa (kelinci/ bulan), sasadara (bulan), nabi (nabi), bumi (bumi), buda (buda/ rabu), iku (ekor), janma (manusia), anak (anak), wani (berani), nyata (nyata), rupa (rupa), dsb. 2) Bernilai dua ialah kata untuk bilangan dua, atau barang yang jumlahnya pada umumnya dua. Kata-kata yang bernilai dua antara lain, paksi (sayap), lar (bulu panjang pada sayap), mata (mata), netra (mata), tangan (tangan), nembah (menyembah), suku (kaki), talingan (telinga), karna (telinga), buja (bahu), dsb. 3) Bernilai tiga ialah kata untuk bilangan tiga, atau api atau barang-barang yang menggunakan api atau berunsur api, atau putri. Kata-kata yang bernilai tiga antara lain, dahana (api), bahni (api), geni (api), agni (api), pawaka (api), tri (tiga), tiga (tiga), telu (tiga), wedha (weda), guna (ilmu pengetahuan), dsb. 4) Bernilai empat ialah kata untuk bilangan empat, atau air, atau barang-barang yang berisi air, atau kata-kata yang bermakna ‘membuat’. Kata-kata yang bernilai empat antara lain, banyu (air), we (air), wedang (air panas), tirta (air), segara (laut) samodra (laut), wahana (sarana), suci (suci), dsb. 5) Bernilai lima ialah kata-kata untuk bilangan lima, atau kata-kata untuk menyebut raksasa (buta), atau kata-kata untuk menyebut senjata tajam seperti panah, anak panah, atau kata-kata yang berunsur angin. Kata-kata yang bernilai lima antara lain buta (raksasa), pandawa (pandawa), tata (tata), 6) Bernilai enam ialah kata-kata untuk bilangan enam, atau unsur-unsur rasa, atau kata-kata yang bermakna ‘bergerak’, yang bermakna ‘kayu’, yang bermakna ‘binatang berkaki enam (sadpada)’. 7) Bernilai tujuh ialah kata-kata untuk menyebut bilangan tujuh, kata-kata untuk menyebut gunung, pendeta (pandhita), kuda, atau menunggang atau mengendarai. 104 8) Bernilai delapan ialah kata-kata untuk menyebut bilangan delapan, kata-kata untuk menyebut gajah, atau binatang melata (reptil), atau pujangga. 9) Bernilai sembilan ialah kata-kata untuk menyebut bilangan sembilan, atau dewa, atau barang-barang yang dianggap berlubang. 10) Bernilai nol ialah kata-kata untuk bilangan nol, atau kata-kata yang bermakna ‘tidak ada’ atau ‘hilang’, atau ‘tinggi’, atau ‘langit’. Dalam bentuk tembang Dhandhanggula, watak bilangan tersebut dituliskan dalam satu bait, sebagai berikut. Janma buweng wani tunggal Gusti (kata-kata yang bernilai 1) / panganten dwi akekanthen asta (bernilai 2) / gegeni putri katlune (bernilai 3) / papat agawe banyu (bernilai 4) / buta lima amanah angin (bernilai 5) / sad rasa kayu obah (bernilai 6) / wiku pitweng gunung (bernilai 7) / gajah wewolu rumangkang (bernilai 8) / dewa sanga anggeganda terus manjing (bernilai 9) / dhuwur wiyat tanpa das (bernilai 0). Menurut Bratakesawa dalam bukunya Candra Sengkala (Padmosoekotjo, tt, Jld. II: 135), ada delapan patokan dalam memilih kata-kata untuk sengkalan, yakni sebagai berikut. 1) Guru dasa nama, yakni kata-kata yang sama artinya atau bersinonim, mempunyai watak bilangan sama. Contohnya kata bumi yang bernilai atau berwatak satu dapat digantikan dengan kata siti, pratiwi, pratala, bantala, kisma, dsb. 2) Guru sastra, yakni kata-kata yang penulisannya atau namanya sama, meskipun artinya berbeda mempunyai watak bilangan sama. Contohnya kata esthi yang berarti ‘maksud’ atau ‘kehendak’ bernilai sama dengan kata esthi yang bermakna ‘gajah’ yakni delapan. 3) Guru wanda, yakni kata-kata yang bersuku kata sama dapat dianggap bernilai sama. Misalnya kata dadi yang berarti ‘menjadi’ sama nilainya dengan kata waudadi yang berarti ‘laut’ yakni bernilai empat. 4) Guru warga, yakni kata-kata yang dapat dikategorikan dalam warga atau jenis atau golongan yang sama dapat dianggap mempunyai nilai yang sama. Misalnya nama binatang jenis reptil mempunyai nilai yang sama. Nilai baya ‘buaya’ sama dengan nilai naga ‘naga’ atau ula ‘ular’ yakni bernilai delapan. 105 5) Guru karya, yakni nama bendanya dianggap sama watak bilangannya dengan hasil kerjanya. Misalnya kata mripat ‘mata’ bernilai sama dengan kata mandeng ‘memandang tajam’, atau ndeleng ‘memandang’, yakni bernilai dua. 6) Guru sarana, yakni nama alat tertentu sama nilainya dengan fungsinya. Misalnya ilat ‘lidah’ sama nilainya dengan rasa ‘rasa’ yakni bernilai enam. 7) Guru darwa, yakni nama benda dengan sifatnya dianggap bernilai sama. Misalnya kata geni ‘api’ bernilai sama dengan kata panas ‘panas’, yakni bernilai tiga. 8) Guru jarwa, yakni kata-kata yang mempunyai kemiripan arti dianggap sama nilainya. Misalnya kata retu ‘tidak tenteram’ atau ‘galau’ bernilai sama dengan kata geger ‘huru-hara’ yakni bernilai enam. Menurut Subalidinata (1981: 96-97), masih ada patokan selain di atas, yakni sebagai berikut. 9) Berdasarkan pertautan nilai angka dalam huruf Jawa, yakni untuk angka 1 atau 7 yakni dengan huruf Jawa ga, dan 8 yakni dengan huruf Jawa pa. Jadi kata lega, raga, boga, dsb dapat bermakna 1 atau 7 karena mengandung bunyi ga. Adapun kata papa, nastapa, wilapa dapat bermakna 8, karena mengandung bunyi pa. 10) Berdasarkan hukum kebiasaan dan kenyataan yang berlaku secara umum. Ratu atau raja ‘raja’, bumi, jagad ‘bumi’ atau ‘dunia’, biasanya hanya satu sehingga bernilai 1. Kata manten ‘pengantin’, tangan ‘tangan’, kuping ‘telinga’ bernilai 2, dsb. 11) Berdasar logika umum, yakni sesuatu yang secara logis dapat dihubungkan dengan nilai angka tertentu. Misalnya kata gandheng ‘bergandeng’ atau ‘bersambung’ dapat bernilai 2. Ilang ‘hilang’ atau musna ‘musnah’ dapat berarti 0, dsb. Contoh-contoh sengkalan adalah sebagai berikut. 1. Rasa rupa dwi sitangsu (tahun 1216, R. Wijaya menjadi raja) 2. Kuda bumi paksaning wong (tahun 1217, pemberontakan Ranggalawe) 3. Brahmana papat muji tunggal (tahun 1748, penobatan Pakubuwana V) 4. Naga iku ngrusak jagad (tahun 1018, Candi Sewu) 5. Sirna ilang gunaning janmi (tahun 1300, Pajajaran runtuh) 106 6. Geni mati siniraming janmi (tahun 1403, Demak berdiri) 7. Tri lunga manca bumine (tahun 1503, Pajang berdiri) 8. Panerus tingal tataning nabi (tahun 1529, Suluk Wujil) 9. Sirneng tata pandhita siwi (tahun 1750, Serat Rama) 10. Atata resi mulang janma (tahun 1795, Serat Centhini). b) Tembang Para Berbeda dengan tembang yasan, tembang para pada umumnya tidak mengenal pupuh. Artinya kesatuan bait-baitnya tidak dapat disebut pupuh karena patokan bait-baitnya tidak konsisten. Jadi pada umumnya, antara bait yang satu dengan bait selanjutnya berbeda-beda pola metrisnya, baik yang menyangkut jumlah barisnya, jumlah suku katanya, maupun persajakannya. Jenis tembang para, antara lain berupa pepindhan yakni menyangkut sanepa, panyandra, isbat, paribasan, bebasan, dan saloka, wangsalan, parikan, lagu dolanan, dan guritan. (1) Pepindhan: Sanepa, Panyandra, dan Isbat Secara luas, sebenarnya kata pepindhan berarti perumpamaan. Dengan demikian sebenarnya pepindhan itu menyangkut sanepa, panyandra, isbat, paribasan, bebasan dan saloka. Kata pepindhan berasal dadi kata dasar pindha yang mengalami perulangan, yakni perulangan dwi purwa salin swara dan mendapatkan akhiran –an. Kata pindha, memiliki sinonim kaya, lir, pendah, lir pendah, kadi, dan kadya yang semuanya beararti ‘seperti’. Jadi pepindhan adalah ungkapan bahasa yang mengandung perbandingan atau perumpamaan. Menurut Padmosoekotjo (t.t., jld. I: 93), perbedaan di antara penamaan beberapa perumpamaan, terutama karena sudut pandangnya. Dari segi pembentukan kalimatnya bisa berupa pepindhan, dari segi isinya bisa berupa panyandra, dari segi diksinya (bregasing basa) bisa berupa basa rinengga, dan dari segi suaranya bisa mengandung purwakanthi, dan seterusnya. Agaknya yang perlu lebih ditekankan adalah antara sanepa, panyandra dan isbat di satu sisi, dan paribasan, bebasan dan saloka di sisi lain. 107 (a) Sanepa Yang disebut sanepa, menurut Padmosoekotjo (t.t., Jld. II: 66), yakni jenis pepindhan yang bentuknya stereortipe (tetap) dan terdiri atas kata sifat yang diikuti kata benda. Sedang menurut Subalidinata (1981: 81) sanepa mengandung arti menyangatkan sesuatu sifat yang diumpamakan dengan cara mempertentangkan. Contohnya sebagai berikut. Ambune arum jamban (baunya, lebih harum comberan dari pada baunya) Balunge atos gedebog (tulangnya lebih keras batang pisang, lunak sekali) Cahyane abang dluwang (air mukanya, lebih merah kertas putih) Eseme pait madu (senyumnya, lebih pait madu) Lungguhe anteng kitiran (duduknya, lebih tenang putaran kipas) Suwe mijet wohing ranti (mudahnya, lebih lama memijat buah ranti) (b) Panyandra Panyandra adalah ungkapan yang mengandung perbandingan dan mengandung persamaan, di dalamnya berisi perbandingan keindahan. Dalam hal ini yang dipentingkan keadaan indahannya, sehingga bahasanya bisa bahasa sehari-hari maupun dengan bahasa indah (basa rinengga). Contohnya sebagai berikut. Athi-athine ngudhup turi (rambut di depan teliunga seperti kuncup turi) Alise nanggal sepisan (alisnya seperti bulan tanggal satu) Bangkekane nawon kemit (pinggangnya bagaikan pinggang tawon kemit) Idepe tumengeng tawang (bulu matanya melengkung ke langit) Kempole ngembang pudhak (betisnya seperti bunga pudak) Lengene nggendhewa pinenthang (lengannya seperti busur dibentang) Ulate ndamar kanginan (air mukanya seperti dian tertiup angin) Untune miji timun (giginyta bagaikan biji mentimun) (c) Isbat Kata isbat berarti ‘ketetapan’. Isbat, yakni ungkapan yang mengandung pengertian tetap, mengandung arti kias, dan pada umumnya bermakna dalam hubungannya dengan tasawuf atau bersifat filosofis-mistis. Contohnya sebagai berikut. 108 Golek banyu apikulan warih (mencari air berpikulan air) Golek geni adedamar (mencari api dengan api) Kodhok ngemuli lenge (Katak menyelimuti liangnya) Nggoleki galihing kangkung (mencari galih pohon kangkung) Nggoleki gigiring punglu (mencari bagian punggung biji asam) Nggoleki susuhing angin (mencari sangkar angin) Nggoleki isining bumbung wungwang (mencari isi bumbung kosong) Nggoleki tapaking kuntul nglayang (mencari jejak burung kuntul terbang) (2) Pepindhan: Paribasan, Bebasan dan Saloka Antara paribasan, bebasan dan saloka memiliki kemiripan bentuk yang pada dasarnya dapat disejajarkan dengan kata peribahasa dalam bahasa dan sastra Indonesia. Paribasan, bebasan dan saloka, ketiganya merupakan kata atau kelompok kata yang mengandung makna kiasan dan bentuknya tetap atau stereotip. Oleh karena kemiripannya, banyak orang yang menyamakan saja antara ketiganya, atau antara pakar yang satu dengan yang lain berbeda dalam hal pemilahannya. Padmosoekotjo (tt, jilid I: 62) menuliskan komentarnya mengenai hal tersebut, yakni bahwa ketiga-tiganya memang sulit dibedakan, bahkan beliau belum pernah mendapatkan atau menemukan penjelasan dari pakar lain yang layak untuk diacu (durung tau mrangguli katrangan sing gumathok lan maremake ingatase beda-bedane). Kemudian beliau mencoba memberikan batasan sebagai berikut. (a) Paribasan Paribasan adalah istilah yang tetap penggunaannya (bunyinya), mempunyai makna kiasan, masing-masing kata tidak mengandung makna kiasan atau pembanding. Sebagai contoh adalah yatna yuwana lena kena. Pada masingmasing kata tersebut tidak mengandung makna kiasan. Kata yatna berarti ‘hatihati’, kata yuwana berarti ‘selamat’, kata lena berarti ‘lengah’, dan kata kena berarti ‘tertimpa’ dalam hal ini ‘tertimpa bencana’. Yatna yuwana lena kena 109 berarti ‘siapa yang berhati-hati akan selamat dan siapa yang lengah akan tertimpa bencana’. (b) Bebasan Bebasan adalah istilah yang tetap penggunaannya (bunyinya), mempunyai makna kiasan, mengandung makna pembanding. Yang dibandingkan adalah keadaan atau sifat orang atau benda tertentu. Orang atau benda yang dikiaskan termasuk di dalamnya, tetapi yang dipentingkan adalah sifatnya. Contohnya kerot ora duwe untu. Kata kerot berarti ‘menggeretakkan gigi bagian atas dengan gigi bawah’. Dalam hal ini kata kerot mengandung makna kiasan yakni bermakna ‘kemauan, keinginan, niat’, atau ‘tujuan’. Kata ora duwe untu berarti ‘tidak punya gigi’. Dalam hal ini ‘tidak punya gigi’ adalah kiasan dari keadaan atau sifat ‘tidak mempunyai biaya atau modal’. Jadi maknanya ‘berniat sekali tetapi tidak mempunyai modal atau biaya’. (c ) Saloka Saloka adalah istilah yang tetap penggunaannya (bunyinya), mengandung makna kiasan, yang dikiaskan adalah orangnya. Sifat dan keadaan orang yang dikiaskan tentu saja termasuk di dalamnya, tetapi dalam jenis ini yang dipentingkan adalah orangnya. Sebagai contoh adalah kebo bule mati setra. Kata kebo berarti ‘kerbau’ bermakna kias ‘orang’. Kata bule berarti ‘jenis orang atau binatang yang berkulit putih karena ras atau kelainan tertentu’ bermakna kias ‘pandai’. Sebagian orang Jawa berkeyakinan bahwa orang bule (termasuk orang Belanda) adalah orang yang pandai. Jadi kebo bule mengiaskan pada ‘orang yang pandai’. Kata mati berarti ‘meninggal’ dan bermakna kias ‘menemui kesengsaraan atau kecelakaan’. Kata setra berarti ‘tempat pembuangan atau kuburan’ bermakna kias sebagai ‘di tempat yang tidak menyenangkan atau tersingkir’. Jadi makna kiasannya adalah orang yang pandai yang tersingkir karena kepandaiannya tidak diperlukan. Peribahasa dalam bahasa Jawa banyak sekali jumlahnya, bisa dibaca dalam buku seperti karya Dirdjosiswojo (1956) dan Darmasoetjipta (1985). Peribahasa Jawa, di samping dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, sering 110 juga diselipkan dalam bentuk-bentuk tembang macapat, dsb. Dalam hal ini peribahasa yang ada kadang kala berubah demi memenuhi tuntutan aturan tembang yang bersangkutan. Sebagai contoh pada pupuh Gambuh dalam Wulangreh karya Pakubuwana IV sebagai berikut. Wonten pocapanipun / adiguna adigang adigung / pan adigang kidang adigung pan esthi / adiguna ula iku / telu pisan mati sampyoh. Pada contoh di atas, peribahasa adigang adigung adiguna berubah karena dibalik menjadi adiguna adigang adigung. Hal ini dikarenakan tuntutan aturan guru lagu yang ada pada tembang Gambuh, yakni baris kedua berakhir dengan bunyi vokal u (aturan seperti itu telah dibicarakan di atas). Bila dikaji lebih lanjut peribahasa Jawa muncul dari latar belakang lingkungan sosial yang berbeda-beda, antara lain sebagai berikut. 1. Lingkungan masyarakat petani. Contohnya sebagai berikut. a. Tatune arang kranjang, artinya ‘lukanya sangat banyak’. b. Arep jamure emoh watange, artinya ‘orang yang hanya mau enaknya tapi tak mau berusaha keras atau bersusah payah’. c. Ambuntut arit, artinya ‘orang yang berwatak tidak baik tetapi tidak terus terang’. d. Anggered pring saka pucuk, artinya ‘kurang bijaksana dengan menentang tradisi’. 2. Lingkungan masyarakat pedagang. Contohnya sebagai berikut. a. Adol lenga kari busik, artinya ‘memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa mengingat kebutuhannya sendiri’. b. Adol gawe, artinya ‘pamer karena ingin dipuji kemampuannya’. c. Adol bagus atau adol ayu, artinya ‘lelaki atau wanita yang sombong’ d. Adol umuk, artinya ‘suka pamer atau sombong’. 3. Lingkungan peradilan dalam masyarakat. a. Anirna daya, artinya ‘mengajukan perkara berdasarkan orang yang telah meninggal’ b. Anirna patra, artinya ‘mengungkiri tulisannya sendiri sebagi bukti peradilan’ 111 c. Anirna pandaya, atinya ‘mengajukan perkara berdasarkan orang yang telah pergi’ d. Akadang saksi, artinya ‘menasihati saksi untuk berkesaksian tertentu’. 4. Lingkungan masyarakat pemburu. a. Amburu kidang lumayu, artinya ‘spekulasi yang sulit berhasil’ b. Ambuwang rase nemu kuwuk, artinya ‘sikap selektif yang merugikan’ c. Nrajang grumbul ana macane, artinya ‘melawan tradisi akan menemui resiko berat’. d. Nemu kuwuk, artinya ‘peristiwa yang bersifat kebetulan’ 5. Lingkungan masyarakat penangkap ikan. a. Amburu uceng kelangan deleg, artinya ‘karena ketamakan untuk mendapatkan berlebih, seseorang menemui kerugian’ b. Iwak kalebu wuwu, artinya ‘menunjuk keadaan terjebak’ c. Uwis kebak sundukane, artinya ‘telah banyak kesalahannya sehingga tertangkap’ d. Enggon welut diedoli udhet, artinya ‘orang yang berlebih dipameri sesuatu yang kurang bernilai sehingga tidak diterima’. e. Kena iwake ora butheg banyune, artinya ‘meraih hasil tanpa dengan merepotkan atau merugikan orang lain’. 6. Lingkungan masyarakat yang lain, misalnya masyarakat pertukangan, peternakan, rumah tangga pada umumnya, dsb. Dalam hal saloka, dalam bahasa Sansekerta maupun bahasa Jawa Kuna sudah ada bentuk yang dalam bahasa Melayu disebut seloka. Namun demikian belum diteliti sejauh mana pengaruh seloka dari kedua bahasa (Sansekerta dan Jawa Kuna) yang sama-sama pernah hidup eksis di Jawa tersebut terhadap saloka bahasa Jawa Baru. Menurut Padmopuspito (1989: 63) ditinjau dari isinya, ketiganya mempunyai kesamaan, yakni mengandung isi yang padat yang merupakan kesimpulan dari berbagai peristiwa dan pengalaman masyarakat yang melatar-belakanginya. Contoh seloka bahasa Sansekerta sebagai berikut. maksikâ vranam icchanti dhanam icchanti pârthivah nîcâh kalaham icchanti çantim icchanti sâdhavah. 112 Artinya: ‘lalat-lalat menginginkan luka, pangeran-pangeran menginginkan kekayaan, orang-orang hina menginginkan percekcokan, orang-orang suci menginginkan ketenangan’. Dalam seloka Sansekerta pada umumnya terdiri atas empat gatra yang sering dijadikan dua baris, masing-masing gatra terdiri atas delapan suku kata, sehingga keseluruhan berjumlah 32 suku kata (setiap baris 16 suku kata). Hal tersebut berbeda dengan seloka Bahasa Jawa Kuna, yang tidak memiliki pola tetap. Contoh seloka Jawa Kuna sebagai berikut. mapa ta phalaning guna, yan enengakena ri unggwanya, yan tan wetwakena, umpamanya, kadyangganing padyut ri jro ning dyun, tan kawedhar padhangnya ring prtiwi mandhala, mangkeha tikang kaprajnân wetwakena juga yan ing prayoganya. Artinya: ‘Apalah hasil kepandaian, jika didiamkan di tempatnya, jika tidak dikeluarkan, umpamanya seperti batang lampu di dalam tempayan, terangnya tidak tersinar di atas bumi, demikian pula halnya dengan kepandaian sebaiknya dikeluarkan saja’ . Dalam saloka bahasa Jawa Baru, seperti halnya dalam bahasa Jawa Kuna, lebih bebas tidak seperti aturan seloka yang ada dalam bahasa Sansekerta. Contoh saloka bahasa Jawa Baru di atas sudah ada yakni kebo bule mati setra. Contoh yang lainnya antara lain: kebo nusu gudel, yang maknanya ‘orang yang tua belajar dari orang yang lebih muda’. Bila ditinjau dari benda yang dipergunakan sebagai kiasan, saloka bahasa Jawa Baru dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yakni sebagai berikut. Pertama, saloka yang mempergunakan binatang. Contohnya sebagai berikut. 1) Gajah ngidak rapah, artinya ‘orang yang melanggar aturannya sendiri’ 2) Kebo mulih ing kandhange, artinya ‘perangtau yang kembali ke asalnya’ 3) Bebek mungsuh mliwis, artinya ‘bermusuhan dengan orang yang lebih mampu’ 4) Kutuk marani sunduk (ula marani gebug), artinya ‘orang yang sengaja memasuki tempat yang berbahaya’ 113 5) Asu belang kalung wang, artinya ‘orang tidak baik yang memiliki andalan kekayaan’ Kedua, saloka yang menggunakan tumbuh-tumbuhan. Contohnya sebagai berikut. 1) Ketepang ngrangsang gunung, artinya ‘cita-cita yang terlalu tinggi dibanding dengan kemampuannya’ 2) Kemladhean ngajak sempal, artinya ’orang yang ditolong atau saudara yang mau menjerumuskan’ 3) Timun wungkuk jaga imbuh, artinya ‘orang tidak mampu yang hanya dipakai sebagai cadangan dalam urusan tertentu’ 4) Cengkir ketindhihan kiring, artinya ‘kalah pengaruh dengan orang yang lebih tua’ 5) Jati ketlusuban ruyung, artinya ‘orang baik yang dipengaruhi oleh orang jahat’ 6) Tunggak jarak mrajak, artinya ‘keturunan orang tidak mampu yang bisa hidup sukses’ 7) Tunggak jati mati, artinya ‘keturunan orang mampu yang tidak sukses’ Ketiga, saloka yang menggunakan benda-benda mati. Contohnya sebagai berikut. 1) Sumur lumaku tinimba (gong lumaku tinabuh), artinya ‘orang yang sangat ingin digurui’ 2) Tigan kapit ing sela, artinya ‘orang lemah dikeroyok orang yang kuat’ 3) Bathok bolu isi madu, artinya ‘orang hina tetapi kaya kepandaian’ 4) Lahang karoban manis, artinya ‘tampan dan berbudi halus’ (Padmopuspito, 1989: 63). (3) Wangsalan Wangsalan adalah bentuk ungkapan yang dinyatakan secara tidak langsung, tetapi hanya dinyatakan melalui bentuk sejenis teka-teki yang memiliki tebusan atau jawaban, dan dalam jawaban itu menyiratkan atau berhubungan dengan maksud ungkapan tertentu. Jadi dalam wangsalan terdapat jawaban tekateki dan maksud ungkapan. Hubungan antara jawaban teka-teki dengan maksud ungkapan, dapat berupa persajakan, kesamaan suku kata, atau kesamaan kata 114 tertentu. Agaknya kata wangsalan berhubungan dengan kata wangsulan yang berarti ‘jawaban’. Menurut Padmosoekotjo (tt, jld. II: 6) wangsalan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yakni sebagai berikut. 1. Wangsalan lamba, yakni wangsalan yang terdiri atas satu kalimat yang terdiri atas dua gatra dan hanya berisi satu jawaban teka-teki. Pada gatra pertama, berisi teka-tekinya dan gatra kedua berisi jawabannya. Contohnya sebagai berikut. Pindhang lulang, kacek apa aku karo kowe. Pada gatra pertama, yakni pindhang lulang, adalah teka-tekinya. Yang dimaksud pindhang lulang, yakni sebagai jawaban teka-teki itu adalah krecek. Pada gatra kedua, yang berupa maksud ungkapannya, berbunyi kacek apa aku karo kowe, terdapat kata kacek. Kata kacek berhubungan dengan kata krecek, yakni dalam hal kesamaan suku kata -cek. 2. Wangsalan rangkep, yakni wangsalan yang isi jawabannya lebih dari satu. Wangsalan ini terdiri atas dua kalimat. Setiap kalimat terdiri atas dua gatra. Pada kalimat pertama terdiri atas dua gatra yang berisi dua teka-teki. Pada kalimat kedua, berisi maksud ungkapannya, yang berhubungan dengan dua jawaban dari dua teka-teki pada gatra pertama. Contohnya sebagai berikut. Jenang sela, wader kalen sesondheran Apuranta, yen wonten lepat kawula. Pada contoh ini, teka-tekinya adalah jenang sela dan wader kalen sesondheran. Yang dimaksud dengan jenang sela adalah apu, dan yang dimaksud dengan wader kalen sesondheran adalah ikan sepat. Baris kedua, merupakan maksud ungkapan, yakni apuranta, yen wonten lepat kawula. Kata apuranta berhubungan dengan kata apu, yakni kesamaan bunyi apu. Sedang kata sepat berhubungan dengan kata lepat, yakni kesamaan bunyi -epat. 3, Wangsalan memet, yakni wangsalan yang dalam menebak maknanya menggunakan langkah dua kali. Sebagai contoh adalah uler kambang, yen trima alon-alonan. Pada contoh ini langkah pertama adalah menebak apa yang dimaksud dengan uler kambang, yakni lintah. Langkah keduanya adalah kata lintah 115 dihubungkan dengan kata alon-alonan melalui kata saktitahe, karena kata saktitahe bersinonim dengan kata alon-alon. Kata alon-alonan merupakan padanan kata saktitahe. Kata saktitahe berhubungan dengan kata lintah, yakni kesamaan suku kata -tah. 4. Wangsalan sehari-hari, yakni wangsalan yang jamak dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Wangsalan jenis ini sering menyebutkan batangan atau jawabannya, dan sering juga tidak menyebutkan jawabannya karena pendengar dianggap telah tahu maksud ungkapannya. Sebagai contoh ungkapan kok njanur gunung ? yang maksudnya kok kadingaren ? Batangan ungkapan janur gunung adalah pohon aren. Contoh lainnya ungkapan mbok aja njangan gori ! Batangan ungkapan njangan gori adalah nggudheg. Maksud ungkapan tersebut adalah agar jangan mbudheg ‘pura-pura tidak mendengarkan’. 5. Wangsalan terpola atau dengan aturan tertentu, yakni 4 wanda (suku kata) + 8 wanda yakni termasuk wangsalan lamba, atau 4 wanda + 8 wanda X 2 baris, yakni termasuk wangsalan rangkep. Contoh yang termasuk wangsalan lamba sebagai berikut. Reca kayu, goleka kawruh rahayu . Reca kayu itu batangan-nya (maksudnya) golek. Ayam wana, ywa nasar tindak dursila. Ayam wana, batangan-nya bekisar. Balung janur, mung sira mangka usada. Balung janur, batangan-nya sada. Carang wreksa, nora gampang nganggit basa. Carang wreksa, batangannya pang. Adapun contoh yang termasuk wangsalan rangkep sebagai berikut. Sayuk karya, wulung wido mangsa rowang Sayektine, wit saking bodho kawula. Sayuk karya maksudnya saiyeg. Wulung wido mangsa rowang maksudnya adalah burung bidho. Balung pakel, gendheo sisaning kalong kari loke, ketanggor padha jarote Balung pakel maksudnya pelok, gendheo sisaning kalong maksudnya sontrot 116 6. Wangsalan edhi-peni, yakni wangsalan yang berupa wangsalan berpola yang termasuk wangsalan rangkep, namun juga menekankan keindahan persajakan (purwakanthi), yakni berupa purwakanthi guru swara (kesamaan bunyi vokal), purwakanthi basa (purwakanthi lumaksita) (kesamaan bunyi pada akhir gatra dengan bunyi yang mengikutinya (di awal gatra berikutnya). Contohnya sebagai berikut. Ancur kaca, kaca kocak munggwing netra den rinasa, tindak mamak tan prayoga Wangsalan tersebut berupa wangsalan terpola (4 suku kata + 8 suku kata), sekaligus berupa wangsalan rangkep (dua baris). Pada baris pertama di akhir gatra pertama terdapat kata kaca yang kemudian diikuti oleh awal gatra kedua yang juga berupa kata kaca (purwakanthi lumaksita). Ancur kaca maksudnya banyu rasa berhubungan dengan kata rinasa, kaca kocak munggwing netra maksudnya tesmak berhubungan dengan kata mamak. 7. Wangsalan yang terdapat dalam bentuk tembang. Wangsalan dalam tembang disesuaikan dengan keperluan aturan dalam tembang yang bersangkutan. Contohnya dalam tembang Kinanthi sebagai berikut. Sang retna tansah anggandrung / anggung amurciteng galih / karan tyasira gung rimang / yen enget angles ing galih / dhuwet alit rerentengan / mung kang mas sun kelayoni (Babad Pasir IX. 24) Batangan dari dhuwet alit rerentengan adalah kelayu. Kelayu berhubungan dengan kata kelayoni. (4) Parikan Tentang arti kata parikan, terdapat dua pendapat yang berbeda yakni sebagai berikut. Pendapat pertama, kata parikan terbentruk dari kata dasar pari yang berarti ‘padi’ mendapat akhiran -an. Namun proses penambahan akhiran an tersebut dilalui dengan proses morfofonemis penambahan fonem glotal stop / k /, sehingga bukan parian tetapi parikan. Kata pari termasuk ragam ngoko yang ragam krama-nya menjadi pantun. Dalam khasanah sastra Indonesia atau Melayu juga terdapat istilah pantun, yang dalam beberapa hal memang mirip 117 dengan bentuk parikan dalan sastra Jawa. Oleh karena itu sering kali jenis parikan Jawa dihubung-hubungkan dengan jenis pantun Indonesia atau Melayu. Pendapat kedua, menyatakan bahwa kata parikan berasal dari kata dasar parik dan mendapat akhiran -an. Kata parik berdekatan arti dengan kata larik yang berarti ‘baris’. Kata parik juga berdekatan arti dengan kata tharik-tharik yang berarti ‘berturut-turut’ atau ‘teratur rapi’ (Padmopuspito, 1989: 69). Menurut Padmosoekotjo (tt, jld. II: 16) parikan mempunyai aturan tiga macam, yakni sebagai berikut. a. Terdiri atas dua kalimat yang dalam ikatannya menggunakan purwakanthi guru-swara (asonansi). b. Tiap kalimat terdiri atas dua gatra. c. Kalimat pertama sebagai sampiran dan isinya terdapat dalam kalimat kedua. Fungsi sampiran adalah untuk menarik perhatian agar yang diajak bicara memperhatikan lebih dulu sehingga benar-benar menangkap isi pesan yang akan disampaikan. Makna kata-kata dalam sampiran kadang-kadang sama sekali tidak berhubungan dengan makna pada bagian isi, namun kadang-kadang juga ada hubungannya. Berdasarkan jumlah suku katanya, parikan dapat dibagi menjadi tiga, yakni sebagai berikut. 1. Parikan yang terdiri atas 4 wanda + 4 wanda X 2 baris. Contoh: Iwak bandeng, durung wayu Priya nggantheng, sugih ngelmu 2. Parikan yang terdiri atas 4 wanda + 8 wanda X 2 baris. Contoh: Kembang adas, sumebar tengahing alas Tiwas-tiwas, nglabuhi wong ora waras 3. Parikan yang terdiri atas 8 wanda + 8 wanda X 2 baris. Contoh: Enting-enting gula jawa, sebungkus isine sanga Kwajibane para siswa, kudu seneng nggubah basa. Parikan yang dua baris itu bisa saja dijadikan empat baris, namun yang jelas terdiri atas empat gatra. Sedang menurut Subalidinata, aturan tersebut di atas masih ditambah dengan persajakannya, yakni gatra pertama bersajak dengan 118 gatra ketiga, gatra kedua bersajak dengan gatra keempat, atau bersajak a b a b (Subalidinata, 1981: 65). Namun demikian bila ditinjau dari contoh-contoh di atas tentu saja variasinya bersajak a a a a. Menurut Subalidinata, parikan seperti contoh pertama di atas bisa dianggap seperti pantun kilat (karmina) dalam sastra Indonesia atau Melayu. Parikan juga sering dipergunakan dalam rangka gerongan, yakni nyanyian yang disertakan dalam lagu-lagu gamelan atau gendhing. Parikan dalam hal ini bersifat luwes, yakni menyesuaikan pada kebutuhan gatra dan wanda dalam gendhing yang bersangkutan. Misalnya parikan pada gendhing dolanan Suwe Ora Jamu (Pelog pathet nem) sebagai berikut. 2 3 3 1 2 3 . . Su we o ra ja mu 1 2 2 3 1 2 . . ja mu go dhong te la 3 5 5 6 6 5 5 4 su we ra ke te mu te mu 4 2 2 1 1 6 . . pi san ga we ge la Pada perkembangannya, dalam percakapan sehari-hari juga sering ditemukan bentuk parikan yang tidak lagi mengikuti aturan yang baku, yakni jumlah wanda-nya lebih bebas. Contohnya sebagai berikut. Ngetan bali ngulon, tiwas edan ora kelakon, atau Si trondhol diedusi, tiwas bodhol jebul mung diapusi, dsb. (5) Guritan dan Geguritan Ada dua pendapat mengenai asal kata guritan. Pendapat pertama, kata guritan berasal dari kata gurit mendapat akhiran -an. Gurit berarti ‘tulisan’ atau ‘pahatan’ atau ‘senandung’. Kata nggegurit dapat berarti ‘menggubah puisi atau bersenandung’. Pendapat kedua, kata guritan terbentuk dari kata gurita dan akhiran -an. Kata gurita berarti ‘tempat tulisan dari kayu’. Jadi guritan 119 merupakan ‘pahatan tulisan pada kayu’. Kiranya dua pendapat tersebut tidak terlalu jauh berbeda, mengingat hasilnya adalah sebuah puisi. Menurut Subalidinata (1981: 47), pada mulanya yang disebut guritan adalah syair dengan persajakan a a a a. Misalnya pada syair Jawa klasik yang berjudul Cohung sebagai berikut. Cohung, cohung, ora gombak ora kuncung anggepe kaya tumenggung e-jreg e-nong, e-jreg e-gung sisir gula jenang jagung Menurut Padmosoekotjo (tt, jld II: 19) pada mulanya yang disebut guritan mempunyai aturan tertentu, yakni sebagai berikut. 1. Jumlah barisnya tidak tertentu tetapi minimal 4 baris. 2. Jumlah suku katanya juga tidak tertentu tetapi setiap baris jumlah suku katanya sama. 3. Persajakan pada akhir barisnya (dhong-dhing) menggunakan purwakanthi guru swara (asonansi) yang sama. 4. Pada banyak guritan, pada awalnya dimulai dengan ungkapan Sun nggegurit, Sun anggurit, Sun gegurit, Sun gurit, atau Sun amarna, dsb. yang bermakna ‘saya mengurit’ atau ‘saya gurit’, atau ‘saya karang’. Contoh: Sun nggegurit: Kaanan jaman saiki sipat pemudha-pemudhi srawungane saya ndadi raket wewekane sepi tan kadi duk jaman nguni srawung sarwa ngati-ati Pada perkembangannya, bentuk lelagon dolanan, meskipun jumlah suku kata pada tiap barisnya tidak tetap, bahkan asonansinya juga tidak tetap, dapat digolongkan sebagai guritan (Padmosoekotjo, tt, jld II: 20). Contohnya lelagon Witing Klapa, sebagai berikut. 5 í 5 2 2 2 5 3 . 120 1 2 1 6 . . . Wit ing kla pa lu gu ne mak sud 5 . 3 . 6 1 2 sung se su luh 2 2 5 ma mrih bi sa 5 5 5 pa ngrip ta . í 6 5 . . . 2 5 6 . 3 pra . . . nu . 6 pik 6 6 sa 6 5 . 6 í mi 2 . 6 . lih 1 a 5 wa 2 kil 3 u 1 ta . ma . . . tu hu bi sa na ta pra ja Pada perkembangan terakhir, muncul istilah geguritan. Pada mulanya geguritan tidak jauh berbeda dengan guritan, namun semakin lama semakin meninggalkan aturan-aturan yang berlaku, hingga menjadi bentuk puisi bebas. Artinya, jumlah barisnya bebas, jumlah suku katanya bebas, persajakannya bebas. Aturan-aturan yang ada dianggap sebagai bentuk yang menjenuhkan, sehingga kalau pun terdapat sisa-sisa aturan yang dirujuk, sifatnya hanya pada bagian-bagian tertentu saja. Misalnya, persajakan yang ada hanya pada barisbaris tertentu, kesamaan jumlah suku katanya hanya pada baris-baris tertentu, dsb. Sebagai contoh geguritan karya I Kunpriyatno, sebagai berikut. Eligi I pelabuhan sepi. Ora ana kapal kang budhal megarake layar. Ora ana kapal kang teka ngoncalake jangkar. Mung ana langit kang timbreng tumelung ing kana. Sajak nyimpen prahara pelabuhan sepi. Ora ana isyarat liwat ora ana sasmita kumlebat. Mung ana ombak dolanan mayit kang bosok ing pasir kuwi. Mayitku : bima kang pralaya mungsuh naga manemburnawa 121 sawise siya-siya nglari sang dewa ruci ing telenging samodra (Jayabaya, No. 36, Minggu II, Mei 2004) 3. Unsur-unsur Puisi Jawa Modern Telah disinggung di atas bahwa secara umum sastra Jawa modern, termasuk di dalamnya puisi Jawa modern, merupakan hasil pengaruh dari sastra Melayu modern yang mengimpor sastra Barat. Dengan demikian kiranya tidak dapat dipungkiri akan perlunya teori-teori yang mendukungnya terutama yang berasal dari Barat, meskipun tidak serta merta teori itu sesuai dengan realitas sastra Jawa. Di samping itu, tidak secara keseluruhan eksistensi puisi Jawa modern merupakan hasil pengaruh dari Barat, karena sejarah kehidupan puisi Jawa modern telah dijalani melalui berbagai kondisi yang ada dalam puisi Jawa tradisional, yang secara umum juga telah memiliki beberapa hal yang tanpa disadari juga ada dalam sastra Barat. Dalam hal puisi Jawa modern, pengaruh dari teori Barat adalah dalam hubungannya dengan struktur puisi dengan berbagai unsurunsurnya, perihal intertekstual, hingga pemaknaan dan semiotiknya. Dalam hal strukturnya, pengaruh itu tampak dalam kebebasan pelarikan hingga pembaitannya termasuk monografinya, penekanan pada diksinya, penggunaan bahasa kiasan, permainan bunyi persajakannya, hingga ritme atau iramanya. termasuk juga pertimbangan persajakannya (purwakanthi), 3 PURWAKANTHI, SASTRA MILIR (SELUIK BELUK SUBALI), JAKAPRADOPO ETIKA PERSAMAAN DAN ETIKA PERBEDAAN 122 3. Sastra Drama Jawa Modern a. Pengertian Drama Suatu hal yang perlu dicatat sebagai langkah awal untuk mengetahui batasan-batasan mengenai karya sastra drama, adalah sebagaimana yang pernah dilakukan oleh para pengamat drama, yakni dengan menelusuri etimologinya. Harymawan (1993: 1) mencatat bahwa istilah drama berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata draomai yang berarti ‘berbuat’, ‘berlaku’, ‘bertindak’, ‘berekreasi’ dsb. Sedang menurut Henry Guntur Tarigan (1984: 69), mengacu pada Morris (1964), istilah drama berasal dari bahasa Greek, yakni dari kata dran yang berarti ‘berbuat’. Dengan demikian, walau sedikit berbeda, pada dasarnya dalam istilah drama terkandung makna ‘berbuat sesuatu’. Istilah lain dari drama yang sering dipergunakan ialah lakon. Menurut Seno Sastroamidjojo (1964: 98), kata lakon berasal dari bahasa Jawa laku yang sering diturunkan menjadi mlaku atau lumaku yang berarti ‘jalan’ atau ‘berjalan’. Kata lakon mengacu pada ‘sesuatu yang sedang berjalan’ atau ‘suatu peristiwa atau kehidupan manusia sehari-hari’. Sedang dalam Kamus Istilah Sastra (1986: 46), lakon berarti karangan berbentuk drama yang ditulis dengan maksud untuk dipentaskan. Di samping lakon, yang merupakan istilah lain dari drama adalah teater. Menurut Tarigan (1984: 73) mengacu pada Encyclopedia Britanica, kata teater adalah alihan dari bahasa Greek theatron yang berarti ‘tempat menonton’. Di Indonesia kata teater sering diartikan sebagai ‘gedung pertunjukan’ atau ‘gedung film’. Namun kadang juga untuk menyebutkan pertunjukan itu sendiri, khususnya drama. Seorang pakar atau pemain drama sering disebut dramawan atau teaterawan. Dalam Kamus Istilah Sastra kata teater, selain berarti drama, juga untuk menyebut kumpulan karya drama. Istilah lainnya lagi yang juga sering dipergunakan ialah tonil atau sandiwara. Tonil merupakan istilah yang berasal dari Belanda, toneel, yang berarti pertunjukan, kejadian atau peristiwa (Kanzannudin, 1995: 84). Menurut Suarsa (1988: 37) daripada mempergunakan istilah sandiwara, para pengamat lebih suka mempergunakan istilah drama. Mbijo Saleh (1967: 2627), menyatakan bahwa istilah sandiwara 123 diciptakan oleh KGPAA. Mangkunegara VII, berasal dari bahasa Jawa sandhi yang berarti ‘rahasia’ dan warah yang berarti ‘ajaran’. Sandiwara berarti pengajaran yang dilakukan dengan perlambang. Menurut Adhy Asmara (1986: 9), istilah sandiwara mulai populer di Indonesia pada Jaman Jepang (1942-1945). Dalam hal ini sandiwara dapat berarti teks drama atau pertunjukan drama. Lebih lanjut Harymawan (1993: 2) menyatakan bahwa drama diartikan sebagai cerita tentang konflik manusia yang dipentaskan di depan penonton dengan dialog-dialog dan aksi. Menurut Japi Tambayong (1981: 15) drama adalah jenis sastra yang tersendiri dan istimewa, cerita yang unik, yang merupakan perenungan akal dan perasaan pengarang, yang bukan sekedar untuk dibaca tetapi dipertunjukkan untuk ditonton. Dalam Kamus Istilah Sastra (Sudjiman, 1986: 20) tertulius bahwa drama adalah karya sastra yang bertujuan menggambarkan kehidupan dengan mengemukakan tikaian dan emosi lewat lakuan dan dialog, lazimnya dirancang untuk pementasan di panggung. Dalam Kamus Istilah Drama (Kanzannudin, 1995: 19) drama adalah (1) segala pertunjukan yang memakai gerak, (2) menurut orang Yunani, berarti pertunjukan atau perbuatan, (3) menurut Aristoteles, berarti gambaran perbuatan atau pertunjukan perbuatan seseorang, (4) menurut Brander Mathews, berarti konflik dari sikap manusia, konflik ini merupakan sumber pokok dari suatu drama, (5) menurut Moulton, berarti hidup yang dilukiskan dengan gerak, (6) menurut Ferdinand Brunotierse, berarti yang melahirkan kehendak manusia sebagai perbuatan atau action, (7) menurut Balthazar, berarti kesenian yang melukiskan sifat dan sikap manusia dengan gerak, (8) menurut Clay Hemilton dan David Koning, sesuatu cerita yang dikarang atau disusun untuk dipertunjukkan oleh para pelaku di atas pentas di depan penonton, (9) menurut LH Hornstein, suatu karya sastra yang ditulis dalam bentuk percakapan dan dimaksudkan untuk dipertunjukkan oleh aktor, (10) pertunjukan sebagai karya seni yang tersusun dari kata-kata yang diucapkan, atau pertunjukan gerakan dengan watak-watak khayal dan mempunyai subyek, laku, perkembangan, puncak, dan konklusi, (11) menurut John E. Dietrich, cerita konfliks manusia 124 dalam bentuk dialog yang diproyeksikan dalam pentas dengan menggunakan percakapan dan akting di depan penonton. Sedang Henry Guntur Tarigan (mengacu pada beberapa pendapat dan beberapa kamus) menyimpulkan tentang drama sbb. 1. Drama adalah salah satu cabang seni sastra 2. Drama dapat berbentuk prosa atau puisi 3. Drama mementingkan dialog, gerak dan perbuatan. 4. Drama adalah lakon yang dipentaskan di atas panggung 5. Drama menggarap lakon-lakon mulai dari penulisan hingga pementsannya 6. Drama membutuhkan ruang, waktu dan penonton 7. Drama adalah hidup yang disajikan dalam gerak 8. Drama adalah sejumlah kejadian yang memikat dan menarik Dalam hubungannya dengan pertunjukan sastra, di samping hal-hal tersebut di atas, hal lain yang juga harus diperhatikan adalah adanya pentas pembacaan puisi (Jawa: tembang dan geguritan) dan pembacaan prosa khususnya cerpen (Jawa: cerkak) yang sering juga dipentaskan di depan penonton. Dalam pembacaannya kadang-kadang juga berkolaborasi dengan musik-musik tertentu sebagai pengiring, sehingga tampak seperti drama. Kenyataan ini sering mengacaukan batasan-batasan drama di atas. Hal lain yang juga harus dicatat adalah bahwa pada kenyataannya terdapat teks drama (lakon) yang terlalu sulit untuk dipentaskan sehingga memang tidak pernah dipentaskan, tapi hanya sebagai bacaan. Hal ini juga terjadi pada jenis lakon yang memang ditujukan untuk dibacakan saja, misalnya lakon untuk drama radio, yang hanya disiarkan melalui media dengar (audio). Dengan demikian kiranya bisa dimengerti adanya pendapat bahwa karya sastra lakon sebenarnya juga bisa dianggap otonom tidak tergantung pada pementasannya, walau tujuan semula pembuatan naskah tersebut untuk dipentaskan. Bagaimanapun juga teks lakon harus diperhatikan secara berbeda dengan pementasan drama di panggung. Oleh karena itu pengamat drama juga harus menempatkan pandangannya dan menyikapi secara berbeda pada kedua seni tersebut. Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud dengan drama adalah karya sastra yang ditulis dengan menekankan bentuk dialog dan lakuan, baik yang 125 ditulis dengan maksud untuk dipentaskan sebagai teater atau yang hanya untuk dibacakan, misalnya sebagai drama radio. b. Drama sebagai Lakon dan sebagai Seni Pertunjukan Seni drama dalam arti luas bukanlah bagian dari seni sastra. Drama merupakan bagian dari seni pertunjukan. Boen S. Oemarjati dalam bukunya Bentuk Lakon dalam Sastra Indonesia menggunakan kata lakon dan teater untuk menunjuk text play atau repertoir atau teks drama tertulis dalam suatu naskah. Sedang H.B. Jassin ketika mengupas sandiwara-sandiwara Usmar Ismail dalam bukunya Sedih dan Gembira, menggunakan ketiga istilah tersebut, di samping juga istilah sandiwara, dalam arti sebagai seni pertunjukan atau performance. Pada kesempatan ini akan dipergunakan istilah lakon atau teks tertulis untuk menyebutkan teks drama tertulis, dan istilah teater atau seni pertunjukan (drama) untuk menyebutkan pementasan drama (penggunaan istilah ini sematamata untuk memudahkan pengertian saja). Kedua jenis seni tersebut (teks lakon dan teater), di sini perlu diperjelas mengingat bahwa dalam khasanah drama di Jawa kedua jenis seni tersebut berbeda namun sangat berhubungan erat dan saling mempengaruhi sejarah perkembangan masing-masing jenis. Menurut Tarigan (1985: 73) ada empat perbedaan pokok antara drama sebagai teks drama tertulis atau lakon, dengan drama sebagai seni pertunjukan, yakni: 1. Drama sebagai teks tertulis adalah hasil sastra milik pribadi (perorangan), yaitu milik penulis drama tersebut; sedang drama sebagai seni pertunjukan adalah seni kolektif. 2. Teks lakon memerlukan pembaca soliter; sedang drama sebagai seni pertunjukan memerlukan penonton kolektif. Penonton menjadi faktor yang sangat penting dalam drama sebagai seni pertunjukan. 3. Teks lakon masih memerlukan penggarapan sebelum dipentaskan menjadi seni pertunjukan 4. Teks lakon adalah bacaan sedang drama sebagai seni pertunjukan adalah tontonan. 126 Perbedaan tersebut membawa berbagai konsekwensi, baik dalam hubungannya dengan penulis maupun bagi pembaca atau penonton. Oleh karena itu Boen S. Oemarjati (1971: 60) menyatakan bahwa seorang penulis lakon dalam menyusun lakon-lakonnya harus senantiasa ingat pada kondisi-kondisi teatrikal (pementasan). Menurutnya, karya sastra yang berbentuk lakon belum bisa dikatakan telah mencapai kesempurnaan bentuk bila belum sampai dipentaskan sebagai seni pertunjukan. Meminjam istilah Luxemburg, dkk. (1989: 159), teks drama berkiblat pada pementasan. Pada kenyataannya makna lakon sering menjadi sangat berbeda dengan makna drama sebagai teater atau seni pertunjukan, walaupun sumber awalnya (teks lakonnya) sama. Hal ini dikarenakan: (1) terjadinya jurang pemisah antara pemaknaan oleh pembaca soliter dengan pemaknaan oleh sejumlah pemain pertunjukan (pembaca kolektif), (2) terjadinya improvisasi di panggung oleh pemain tertentu, (3) penggarapan teater menyimpang dari teks lakonnya, yang sengaja dilakukan oleh sutradara dan para pemain pertunjukan drama. Teks lakon sering dipentaskan dengan penggarapan yang menyimpang. Hal ini antara lain dikarenakan: (1) Disesuaikan dengan latar belakang sosial budaya di tempat pementasan drama tersebut. (2) Disesuaikan dengan visi dan misi sutradara atau kelompok drama yang bersangkutan. (3) Karena permintaan dari pihak-pihak tertentu, misalnya kepolisian atau pemerintahan penguasa. (4) Karena pertimbangan nilai jual (mengacu pada penonton). Oleh karena itu sering terjadi perubahan dari naskah lakon yang berisi cerita klasik dipentaskan dalam bentuk modern, dari naskah lakon yang serius dipentaskan menjadi komedi, dsb. Berdasarkan uraian di atas, kiranya menjadi jelas bahwa, sekali lagi, teks lakon harus dibedakan dengan teks pementasan (teater), karena sistem dan tingkat pemaknaannya yang memang berbeda. 127 c. Unsur-unsur Drama Drama sebagai tontonan sering memiliki berbagai unsur seni. Sebagai contoh dalam pertunjukan wayang purwa terkandung unsur-unsur seni sastra, seni musik, seni lukis, seni pahat, seni gerak/ tari, seni suara, seni panggung, dan sebagainya. Seni sastra wayang tampak pada kandungan ceritanya, seni musiknya tampak pada seni karawitannya, yakni penggarapan gendhing-gendhing-nya (musik gamelan), seni lukisnya tampak pada gambar dan permainan warna cat pada wayangnya, seni pahatnya tampak pada model seni tatahan boneka wayangnya, seni tarinya tampak pada keterampilan dalang dalam menggerakkan boneka wayangnya, seni suaranya tampak pada suara dalang, suara para niyaga, dan suara para pesindennya, sedang seni panggungnya tanpak pada cara mengatur posisi perangkat gamelan, posisi simpingan wayang, posisi dalangnya, posisi pesindennya, dan sebagainya yang semuanya disesuaikan dengan kepentingan artistik dan fungsi lainnya. Berbagai unsur seni tersebut, di dalamnya masih banyak unsur-unsur yang lebih kecil yang memerlukan pembicaraan tersendiri. Namun demikian di bawah ini akan ditekankan unsur-unsur drama yang merupakan bagian dari seni sastranya. Dalam rangka seni sastranya, secara tertulis ada beberapa unsur penting dalam drama yang perlu dibicarakan, antara lain (1) teks samping dan teks pokok, (2) alur, pembabakan dan adegan, (3) dialog, lakuan dan penokohan, (4) seting atau latar, (5) tema dan (6) amanat. Disamping itu masih ada hal yang perlu diperhatikan dalam drama, yakni konvensi yang mengikatnya. Hal ini terutama karena karya sastra drama ditujukan kepada orang lain untuk dibaca dan atau dipentaskan, sehingga terdapat konvensi yang mengikat di antara mereka. 1) . Teks Samping dan Teks Pokok Apabila dicermati lebih lanjut, sebenarnya dalam drama, dapat ditemukan dua jenis teks, yakni (1) teks yang berisi dialog-dialog atau monolog para pelaku, dan (2) teks yang berisi berbagai keterangan atau penjelasan tentang pelaku dan lakuannya, termasuk keterangan tentang berbagai pengiring pelaku dan lakuannya. Jan Van Luxeburg, dkk. (1989: 164-167) menyebutkan kedua jenis 128 teks tersebut sebagai teks pokok dan teks samping. Teks pokok adalah teks yang berisi dialog dan monolog, sedang teks samping adalah teks yang berisi berbagai keterangan atau penjelasan tentang teknis pementasannya, yang mendukung teks pokok. Pada bentuk drama tertulis atau lakon, teks samping yang berisi tentang berbagai penjelasan tersebut, sifatnya asli dan terbatas. Asli artinya dibuat oleh pembuat naskah lakon. Sedang yang dimaksud dengan terbatas adalah hanya terbatas oleh apa yang dituliskan dalam teks lakon itu saja. Sedang pada bentuk seni pertunjukan, bila pertunjukan tersebut ditranskripsikan, teks samping akan diisi oleh penonton atau pengamat sebagai suatu laporan secara cermat dan lengkap. Semakin cermat pengamatan akan semakin lengkap transkripsi teks sampingnya. Oleh karena itu teks samping dalam seni pertunjukan sudah merupakan hasil pengamatan penonton atau bahkan merupakan penafsiran penonton dari penafsiran sutradara dan pemain teater. Oleh karena itu pula sifatnya sudah tidak asli dan sangat mungkin banyak perubahan-perubahan atau tambahan-tambahan dari teks samping dalam teks lakonnya. Pembicaraan tentang teks samping dan teks pokok menjadi penting mengingat makna drama, yang sangat ditentukan oleh lengkap tidaknya intensitas teks samping. Pada kenyataannya terdapat drama yang hanya berisi dialog-dialog saja, sama sekali tidak ada teks sampingnya. Pada bentuk seperti ini Luxemburg dkk. menyebutnya sebagai drama mutlak. Dalam drama mutlak, oleh karena tanpa teks samping sama sekali, maka konsekwensinya, berbagai penjelasan yang mestinya diperlukan, secara bebas boleh diisi oleh pembaca sebagai hasil dari penafsiran dari teks pokoknya. Dengan demikian makna pada bentuk drama mutlak, relatif sangat multi interpretabel, sangat beragam tergantung para pembaca sebagai penafsirnya. Sebaliknya, drama yang mengandung teks samping yang sangat lengkap dan detail, maknanya sangat ditentukan oleh drama itu sendiri. Semakin lengkap dan detail teks sampingnya, akan semakin menentukan penafsiran maknanya, sehingga keberagaman pemaknaan drama tersebut juga semakin terbatas. 2). Alur, Pembabakan dan Adegan-adegannya 129 Alur adalah jalinan peristiwa di dalam karya sastra untuk mencapai efek tertentu. Pautannya dapat diwujudkan oleh hubungan temporal dan hubungan kausal. Alur adalah rangkaian peristiwa yang direka atau dijalin dengan seksama, yang menggerakkan cerita melalui rumitan ke arah klimaks dan selesaian (Sudjiman,1986: 4). Alur mempunyai bagian-bagian yang dapat dikenali sebagai permulaan, pertikaian, perumitan, puncak, peleraian dan akhir. Dalam permulaan pengarang memperkenalkan tokoh-tokohnya. Akibat hubungan antar tokoh, terjadilah peristiwa dan timbulah pertikaian, baik pertikaian lahir maupun pertikaian batin dalam diri tokoh. Dalam perumitan mulai diungkapkan persentuhan konflik, perbenturan antara kekuatan-kekuatan yang berlawanan. Kemudian terus menggawat sampai klimaks. Klimaks atau puncak merupakan kelanjutan logis dari perumitan atau penggawatan, kelanjutan dari penggawatan jaringan konflik secara wajar atau masuk akal. Puncak itu memerlukan penyelesaian sebagai peredaannya. Di puncak itulah diungkapkan pergumulan konflik dengan tegangan paling kuat. Dari puncak itu, cerita menuju akhir, baik melalui peleraian ataupun tidak, karena puncak itu sendiri bisa menjadi akhir cerita. Dengan kata lain akhir cerita tidak selalu berupa penyelesaian permasalahan (Mido, 1982: 11). Alur dalam drama sedikit berbeda sarananya bila dibandingkan dengan alur pada jenis sastra prosa. Ada dua macam perbedaan yang mendasar. Pertama, dalam bentuk prosa biasanya alur dibangun melalui kisahan atau ceritaan atau narasi, sedang dalam drama, pada umumnya alur dibangun melalui adeganadegan dan pembabakan yang di dalamnya berisi dialog-dialog atau lakuan para pelaku. Oleh karena itu struktur adegan menjadi sangat penting untuk menentukan permainan alur agar suatu drama menjadi lebih menarik dan tidak membosankan dari segi perkembangan alurnya. Kedua, permainan alur dalam drama tidak seluwes dalam bentuk prosa. Dalam prosa, alur dapat dipermainkan dengan leluasa, dibolak-balik linearitasnya, sehingga bisa dilakukan sorot balik secara berulang-ulang. Dalam bentuk drama, secara teknis hal semacam itu menyulitkan, baik teknis pementasannya maupun kemungkinan keberterimaan penontonnya. Perlu diingat bahwa menonton informasi yang sama hanya bisa 130 terjadi sekali, sedang dalam membaca informasi yang sama bisa diulangi berkalikali. Pada umumnya dalam drama tradisional, alur disusun secara urut sebagaimana alur linear yang ditentukan oleh urutan waktu kejadian. Apabila diperlukan pengisahan tentang peristiwa yang terjadi di waktu yang lampau, cukup dilontarkan atau diceritakan oleh seorang atau beberapa pelaku, tanpa harus diadakan lakuan secara langsung. Dalam drama modern hal semacam itu bisa disiasati dengan menampilkan lakuan secara langsung berbagai kejadian yang latar waktunya lebih lampau, baik dengan menggunakan petunjuk atau tanda adanya flash back dalam dialog, maupun tidak. Bila tidak, tentu saja dialog-dialog didalamnya diharapkan dapat mewakili penjelasan bahwa kejadiannya merupakan kejadian di masa lampau. Jadi dalam drama tradisional, pada umumnya alur dibangun secara setia dari latar waktu yang awal, tengah, hingga waktu terakhir. Dalam drama dikenal istilah permulaan atau eksposisi, pertengahan atau komplikasi dan akhir atau resolusi. Pada tahap eksposisi, dipaparkan berbagai kejadian awal yang menjadi latar belakang terjadinya berbagai peristiwa di babak selanjutnya. Pada tahap komplikasi disuguhkan berbagai konflik serta perkembangannya. Di sinilah terjadi pertemuan antar berbagai visi dan misi dari tokoh-tokohnya, sehingga terjadi konflik-konflik. Konflik tersebut semakin memuncak hingga mencapai klimaks, yang kemudian mendapatkan pemecahan-pemecahan atau peleraian. Tahap peleraian inilah yang disebut sebagai tahap resolusi. Alur yang demikian itu biasanya digambarkan sbb. Klimaks Komplikasi Eksposisi Peleraian Permulaan Akhir 131 Bagian klimaks biasanya ditandai dengan kejadian yang merupakan titik perubahan penting atau crucial shift bagi nasib atau perilaku atau keberhasilan tokoh-tokoh utamanya. Sedang bagian akhir suatu drama, ditinjau dari nasib tokoh utamanya, bisa digolongkan menjadi dua macam, yakni berakhir bahagia (happy ending) atau tidak (unhappy ending). Ditinjau dari penyelesaiannya, seperti halnya pada jenis prosa fiksi, drama juga bisa berakhir dengan penyelesaian segala permasalahan yang dikembangkan di bagian depan, namun juga bisa berakhir dengan isyarat masih adanya permasalahan atau dibukanya permasalahan baru. Sebagai contoh pada drama yang, misalnya, diberi judul Drakula di Kota Bandung, bisa saja diakhiri dengan membunuh drakulanya. Namun ketika drakula itu terkapar sekarat, seorang kurir memberitakan pada tokoh utamanya bahwa saudaranya yang di Jakarta, menelephon dengan suara terengah-engah, karena sedang dikejar drakula yang lain. Ketika tokoh utamanya tercengang, drama itu berakhir. Contoh lain, pada drama wayang purwa kadang terjadi pada akhir cerita disebutkan bahwa suatu kejadian akan terjadi pada lakon lain. Lakon kematian Kala Bendana diakhiri oleh cerita dalang bahwa sukma Kala Bendana akan tetap menanti Gathutkaca hingga kelak pada lakon Gathutkaca Gugur (kematian Gathutkaca). Lakon Pendhawa Dhadhu diakhiri oleh cerita dalang bahwa sumpah drupadi (bahwa ia tidak akan mandi keramas bila belum keramas dengan darah Dursasana) akan berakhir bila ada lakon Dursasana Gugur, dsb. Penentuan pembabakan dan adegan-adegan dalam drama tergantung pada permasalahan yang dibangun dan latar tempat yang ada dalam cerita. Pada umumnya setiap latar tempat yang berbeda bisa dijadikan sebagai adegan baru, karena di tempat itu lakuan dan dialog tokoh-tokohnya juga berbeda dengan di tempat lain. Sedang pembabakannya ditentukan oleh kesatuan permasalahan dan tempatnya sekaligus, sehingga bisa dipisahkan dengan babak yang lain. Dalam satu babak bisa saja berisi satu adegan, namun juga bisa berisi beberapa adegan. Dalam wayang purwa, misalnya, babak pertama biasanya berisi adegan di istana, lalu adegan di keputren (kedhatonan) (ruang permaisuri), dan adegan di paseban jawi (di luar istana) atau di alun-alun. Oleh karena itu satu kesatuan cerita bisa 132 saja dijadikan menjadi satu babak saja atau beberapa babak. Bila terbagi menjadi beberapa babak, bisa dipentaskan dalam satu malam, tapi juga bisa dipentaskan dalam beberapa malam. 3). Dialog, Lakuan dan Penokohan Di atas sudah disinggung bahwa setiap adegan dalam drama berisi lakuan dan dialog para tokohnya. Dialog dalam drama berfungsi sebagai penggerak alur cerita drama. Di samping itu, dialog dalam drama merupakan cerminan dari penokohan, bahkan sebenarnya penokohan dalam drama dapat ditentukan oleh dialognya saja, tanpa harus dicari dari penjelasan lain. Hal ini terbukti dengan adanya teks drama yang disebut drama mutlak, yang hanya berisi dialog-dialog, tanpa adanya teks samping. Oleh karena itu dalam drama mutlak, secara ideal menuntut kelengkapan dialog. Hal ini merupakan keunggulan sekaligus kelemahan drama mutlak. Keunggulannya drama mutlak bersifat luwes, karena sutradara dan pelaku lebih bebas menafsirkan lakuannya. Kelemahannya, menuntut konsekwensi lebih lanjut, yakni kelengkapan dialog sehingga terlalu panjang dan bertele-telenya drama. Hal ini berakibat sangat membosankan. Dengan demikian tidak mengherankan bila pada umumnya drama memerlukan teks samping untuk mewadahi berbagai penjelasan yang tidak perlu ditampilkan secara langsung dalam pementasannya. Oleh karena itu pula dialog dalam drama harus efektif dan efisien, artinya harus benar-benar mampu menjelaskan secara tuntas berbagai visi dan misi dalam dialog yang sesingkat-singkatnya, serta sekaligus harus harus mempertimbangkan kewajaran atau bersifat alamiah. Sehubungan dengan hal di atas, menurut Tarigan (1985: 77), dialog dalam drama harus memenuhi dua hal, yakni dapat (1) mempertinggi nilai gerak, artinya dialog harus wajar tapi menarik, harus mencerminkan pikiran dan perasaan para tokohnya dan (2) harus baik dan bernilai tinggi, artinya harus lebih terarah dan teratur dari pada percakapan sehari-hari. Jadi dialog harus jelas, terang dan menuju sasaran. Dari uraian tersebut tampak sekali bahwa dialog dalam drama menduduki peranan terpenting. Penokohan dalam drama, disamping dituangkan dalam bentuk dialog, juga dijelaskan dalam teks samping yang berisi pemerian tentang ciri-ciri dan 133 lakuan tokoh yang bersangkutan, misalnya penamaannya, jenis kelaminnya, usianya, bentuk tubuhnya, potongan rambutnya, bentuk bibirnya, dsb., serta bagaimana gerak dan tingkah laku tokoh yang bersangkutan dalam setiap dialog, setiap adegan, setiap babak, hingga keseluruhan cerita drama. Lakuan tokohtokoh dalam drama dapat dituliskan dalam teks samping secara panjang lebar atau diperikan hingga sejelas mungkin, tapi juga bisa hanya diperikan garis besarnya saja. Bila dituliskan secara terperinci, penokohannya menjadi semakin jelas, namun akan lebih sulit dilaksanakan dalam pementasan. Sebaliknya, bila lakuan itu tidak diperikan secara detail, penokohannya sangat tergantung dari penafsiran subyektif pembacanya, namun lebih mudah pelaksanaan pementasannya. Penokohan dalam drama, sama seperti dalam bentuk fiksi prosa, dapat dibagi menurut peranannya dalam keseluruhan cerita sehingga dikenal tokoh utama, tokoh andalan dan tokoh bawahan. Tokoh utama yakni tokoh yang secara intensif menduduki peranan penting yakni sebagai tokoh sentral dalam tema pokok cerita. Tokoh andalan adalah tokoh yang berperanan membantu tokoh utama untuk menyampaikan pikiran-pikiran dan perasaan tokoh utama. Tokoh andalan ini biasanya dihadirkan untuk menghindari monolog pada tokoh utama. Sedang tokoh bawahan adalah tokoh-tokoh yang tidak berperanan penting dalam hubungannya dengan tema pokok, tetapi diperlukan untuk membantu memperjelas pokok-pokok pikiran dalam cerita, membantu perumitan alur sehingga lebih estetis sekaligus lebih realistis. Lebih estetis maksudnya alurnya tidak terlalu sederhana sehingga tidak mudah ditebak kelanjutannya. Lebih realistis maksudnya tidak didominir oleh tokoh utama saja. Dalam hubungannya dengan tujuan hidup, cita-cita atau perjuangan tokoh utama dapat dibagi menjadi tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh protagonis lazimnya disamakan dengan tokoh utama. Sedang antagonis adalah tokoh yang selalu melawan atau menghadang tujuan hidup, cita-cita atau perjuangan protagonis. Dalam drama Jawa tradisional, tokoh-tokoh protagonis dan antagonis sengaja dibedakan secara sangat jelas dalam penampilannya, baik tingkah lakunya, cara berbicara, cara berpakaian, make up-nya, dan sebagainya. Tokoh 134 protagonis identik dengan kehalusan sedang tokoh antagonis selalu serba kasar, baik fisik maupun tingkah laku. Dalam jenis kethoprak, tokoh-tokoh antagonis sering disebut brasak atau brasakan, selalu digambarkan sebagai tokoh yang kasar, make up dan asesorisnya serba kasar dan berlebihan, bila tertawa terbahakbahak, bertindak dan berbicara dengan keras dan kasar, egois, dan sebagainya. Sedang tokoh protagonis yang diwakili oleh tokoh bambangan alus, selalu tampil dengan halus, make-up dan asesoris sederhana, berbudi pekerti halus dan ideal. Dalam wayang purwa tokoh-tokoh kesatria protagonis diikuti oleh tokoh-tokoh Panakawan, yakni Semar, Gareng, Petruk dan Bagong dan dikategorikan sebagai satriya tanah Jawa. Tokoh-tokoh kesatria halus sering digambarkan lebih kecil dan halus. Sedang tokoh-tokoh antagonis diikuti oleh abdi Togog dan Mbilung (Saraita). Tokoh-tokoh antagonis sering digambarkan sebagai tokoh yang berasal dari sabrang atau tokoh sabrangan. Biasanya tokoh-tokoh sabrang digambarkan sebagai raksasa yang relatif lebih besar dari para kesatria halus. Tokoh antagonis juga berada di pihak para Korawa yang juga serba kasar, egois, dsb. Menurut perkembangan watak dan nasib hingga perkembangan kejiwaannya dapat dikenal tokoh bulat dan tokoh pipih. Tokoh bulat adalah tokoh yang karena nasibnya membuat perwatakannya hingga kejiwaannya berkembang, bahkan bisa bertolak belakang. Contohnya, tokoh yang semula berwatak baik, karena keadaan tertentu menjadikan wataknya dan kejiwaannya berkembang hingga menjadi tokoh yang berwatak buruk. Sedang tokoh pipih atau sering disebut juga tokoh datar, adalah tokoh yang perkembangan perwatakannya relatif kecil atau bahkan tidak berkembang sama sekali. Menurut Kuntowijoyo (1984: 127-129), dalam sastra tradisional, perwatakan tokohtokohnya, relatif tidak dikembangkan kejiwaannya karena perwatakan tokohtokoh tersebut terbentuk lebih dahulu oleh tipe-tipe ideal dalam masyarakatnya. Dengan demikian relatif perwatakannya datar atau pipih. Penggambaran tersebut sesuai dengan penokohan dalam drama-drama tradisional, khususnya dalam wayang purwa. Dalam wayang purwa penokohan semacam itu memang menjadi ciri khasnya. Dengan kata lain tokoh-tokoh dalam wayang purwa tidak ditekankan dari sisi psikologisnya tetapi dari sisi perkembangan kejadiannya. Hal ini akan dijelaskan lagi dalam bagian yang membicarakan tentang wayang purwa. 135 Tentu saja, penokohan tersebut sedikit berbeda dengan yang terjadi dalam drama tradisional yang berupa kethoprak. Hal ini dikarenakan sejumlah lakon kethoprak diambil dari cerita babad yang notabene merupakan sejarah yang pernah terjadi. Dengan demikian penokohannya relatif lebih beragam perkembangannya dan sebagian besar tidak ditentukan atau tidak didikte oleh idealisme masyarakatnya, namun lebih ke arah realitas. 4). Latar atau Seting Latar atau seting, merupakan dasar pijak atau landas tumpu bagi peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Secara umum, latar dapat dibagi menjadi empat, yakni latar tempat, latar sosial, latar waktu, dan latar suasana. Latar berfungsi membantu memberikan pencitraan tokoh-tokohnya (penokohan) secara tidak langsung. Misalnya tokoh-tokoh yang berwatak buruk dan keras bisa dibantu pencitraannya melalui latar yang serba tidak teratur, berantakan, gersang, di kolong jembatan, di keramaian kota, siang hari yang panas, kegerahan, dsb. Cara penggambaran latar dalam drama sedikit berbeda dengan sastra prosa, karena tujuan penulisannya yang diperuntukkan sebagai pentas di panggung. Oleh karena tujuan itu, latar dalam drama dapat dibagi menjadi dua, yakni: (1) yang ditujukan untuk sutradara dan para pemain drama dan (2) yang ditujukan untuk para penonton. Pada umumnya latar dalam drama dituliskan dalam teks samping sebagai keterangan pemandu bagi sutradara dan pemain drama. Namun demikian, khususnya berbagai hal yang berhubungan dengan suasana yang tidak cukup dijelaskan dalam teks samping, harus dimunculkan dalam bentuk dialog. Dalam teks samping, latar hanya dituliskan pada bagian sebelum atau awal adegan atau awal babak saja. Karena tujuannya dipanggungkan, tentu saja jarang ada penggambaran latar tempat dalam drama yang terjadi di perjalanan, yang pada realitas kehidupan sering berpindah-pindah dan berubah-ubah karena bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Hal yang demikian itu hanya bisa dimainkan dalam drama yang bermedia film, drama radio, atau dimunculkan dalam bentuk dialog sebagai penjelasan bagi penonton atau pendengar. 136 Dalam drama panggung terdapat konvensi yang menyatakan bahwa suatu peristiwa terjadi pada saat itu dan di situ (pada saat dipentaskan itu dan di panggung yang bersangkutan itu). Dalam panggung wayang purwa, sering kali sang dalang mengatakan bahwa padha papane amung beda caritane awit dumadi saka sapanggung (sama tempatnya berbeda ceritanya karena terjadi dalam satu panggung). Dalam hubungannya dengan hal itu, bila drama itu hanya ditujukan untuk dipentaskan di panggung, suatu latar tempat yang berupa nama tempat atau latar waktu yang berupa nama hari tertentu atau jam tertentu, atau latar suasana tertentu, yang ditekankan secara khusus, agar dapat diketahui penonton drama yang bersangkutan, maka perlu disebutkan oleh tokoh-tokohnya dalam bentuk dialog pada adegan masing-masing. Misalnya suasana mistis pada malam Jumat Kliwon yang bagi latar sosial tertentu, seperti suku Jawa, mengandung makna khusus, tentu saja tidak cukup dituliskan dalam teks samping, jadi perlu dilontarkan melalui dialog bahwa saat itu malam Jumat Kliwon. Latar suasana yang demikian itu bisa dibantu dengan berbagai lakuan seperti membakar kemenyan, dsb., yang dapat dijelaskan atau dituliskan dalam teks samping. 5). Tema dan Amanat dalam Drama Penulis naskah lakon, mencipta bukanlah semata-mata mencipta, tetapi untuk menciptakan pesan atau amanat kepada masyarakat, kepada bangsa, bahkan kepada seluruh manusia dan kemanusiaan. Penulis naskah lakon mencipta untuk menyuguhkan persoalan kehidupan manusia, baik kehidupan batiniah maupun lahiriah, yakni pikiran (cipta), perasaan (rasa), dan kehendak (karsa). Teknik penyampaian pesan itu dapat secara langsung atau tidak langsung, tersurat, tersirat atau simbolik (Satoto, 1985: 16). Adapun tentang tema, M. Saleh Saad menyatakan bahwa tema karya sastra adalah sesuatu yang menjadi pikiran pokok, sesuatu yang menjadi persoalan bagi pengarang. Di dalamnya terbayang pandangan hidup atau citacita pengarang, cara ia melihat persoalan itu. Persoalan itulah yang dihidangkan pengarang, yang kadang-kadang dihadirkan pemecahannya sekaligus. Pemecahannya itulah yang diistilahkan dengan amanat (Mido, 1982: 9). Kalau tema dalam lakon merupakan ide sentral yang menjadi pokok persoalannya, 137 maka amanat merupakan pemecahannya. Tema dan amanat dalam seni sastra sebaiknya disesuaikan dengan kondisi lingkungannya (Satoto, 1985: 16). Dalam drama Jawa sebagian besar tema-tema yang ada bersifat istana centris, baik yang bersumber pada cerita wayang purwa maupun yang diambil dari sumber serat-serat babad. Tema-tema istana centris inilah yang sering dipentaskan dalam drama-drama tradisional Jawa, seperti dalam berbagai jenis drama wayang dan kethoprak. Adapun tema-tema modern yang mengetengahkan kehidupan masyarakat modern mulai tergarap sejak munculnya drama Jawa modern atau sandiwara modern yang keberadaannya telah mendapat pengaruh dari budaya drama bangsa-bangsa Barat. Amanat pada jenis lakon wayang pada umumnya, teknik penyampaian pesannya menggunakan cara simbolik. Wayang itu sendiri merupakan karya seni yang bersifat simbolik (Satoto, 1985: 16). Jalan cerita wayang secara simbolik juga mengandung amanat, namun juga tidak tertutup kemungkinan penyampaian amanat secara eksplisit, antara lain berupa ajaran yang disampaikan oleh seorang pandita kepada seorang kesatria (setelah adegan gara-gara), disampaikan oleh tokoh-tokoh abdi kepada sesama abdi (pada adegan gara-gara atau limbukan), abdi kepada tuannya (adegan sabrangan atau adegan kesatria), atau abdi kepada masyarakat penonton secara langsung (adegan limbukan atau gara-gara). Bahkan setiap tokoh mungkin saja dibebani amanat oleh pengarang atau dalang. Menurut Wibisono (1987: 8) semakin akrab dengan konvensi pedalangan akan semakin mudah untuk membaca amanat yang tersurat maupun yang tersirat dalam lakon wayang. 6). Konvensi dalam Drama Yang dibicarakan di atas, pada dasarnya merupakan unsur-unsur yang secara teoritis termasuk dalam unsur struktur intrinsik drama. Masih ada unsur lain yang sesungguhnya tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan dalam memahami drama, yakni yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat pendukang drama yang bersangkutan. Unsur yang dimaksud adalah konvensi dalam drama. 138 Teks drama ditulis dengan mengacu pada kemungkinan pementasannya. Pementasan drama, di samping harus mempertimbangkan berbagai inovasi pembaharuan, juga harus selalu mengacu pada berbagai aturan main yang telah bersifat konvensional dalam pementasan-pementasan sebelumnya. Hal ini menjadikan teks drama sangat terikat pada berbagai konvensi yang ada, baik konvensi penulisan maupun konvensi yang ada dalam pementasan. Di samping konvensi yang bersifat umum sebagai seni pertunjukan, setiap jenis drama memiliki kekhasannya masing-masing dalam hubungannya dengan konvensi yang melekatinya Dalam bentuk drama tradisional, konvensi yang ada dalam pementasan akan semakin dipatuhi pada saat menulis maupun mementaskan drama. Hal ini dikarenakan penulis dan pemain drama tradisional mengacu pada kemungkinan keberterimaan masyarakat pada apa yang dihasilkannya. Inovasi dalam drama tradisional, pada umumnya hanya dapat diterima bila inovasi tersebut berada pada unsur-unsur atau bagian-bagian tertentu yang memang tersedia untuk dipakai sebagai unjuk kebolehan dengan berbagai inovasi. Dalam drama Jawa tradisional, wayang purwa misalnya, struktur drama wayang purwa sangat terikat oleh berbagai konvensi yang ada dalam tradisi yang bersangkutan (Wibisono, 1987: 8). Dalam wayang purwa dikenal beberapa tradisi yang ada di Jawa, antara lain tradisi Surakarta, tradisi Yogyakarta, tradisi Banyumasan, dan tradisi pesisiran. Berbagai konvensi dari masing-masing tradisi yang ada dalam wayang purwa, pada gilirannya akan tampak menonjol pada setiap unsur dramatiknya, baik dalam rangka pementasannya maupun dalam teks sastranya. Dalam drama modern, konvensi yang ada relatif lebih sedikit dibanding dengan jenis-jenis drama tradisional. Oleh karena itu di sana-sini sangat terbuka untuk disisipkan inovasi. Bahkan berbagai konvensi yang ada sangat rentan untuk diabaikan atau bahkan diberontaki. Namun demikian bukan berarti bahwa dalam drama modern tidak ada konvensi yang berlaku, karena setiap jenis drama akan mengacu pada tujuan dan fungsinya yang berhubungan dengan masyarakat. Dengan demikian keberterimaan masyarakat akan selalu menjadi titik tolak yang diperhitungkan. Hal itulah yang menjadi tempat berperannya konvensi drama. 139 d. Sejarah Singkat Drama Jawa Jenis drama, khususnya drama Jawa tidak banyak dibicarakan orang. Namun demikian pada kenyataannya, seperti yang pernah dikatakan Sumardjono, penulis naskah sandiwara RRI Yogyakarta (Via Hutomo, 1983: 62), orang-orang Jawa mengenal sastra Jawa, baik cerita wayang maupun babad, sebenarnya melalui drama, yakni drama tradisional, wayang purwa, wayang wong, kethoprak dan sebagainya. Drama dalam pengertian yang luas, yakni sebagai seni pertunjukan, sebenarnya telah lama sekali dikenal di Jawa, khususnya drama wayang. Ir. Sri Mulyono dalam bukunya Wayang: Asal-usul, Filsafat dan Masa Depannya (1978), mengumpulkan berbagai pendapat yang menyatakan bahwa drama wayang telah ada sejak zaman Jawa Kuna, antara lain yang terdapat dalam prasasti Balitung (907 M) yang menuliskan “mawayang buat Hyang” dan adanya lakon “Bhimaya Kumara”. Sebelumnya, yakni pada prasasti Jaha (tahun 840 M) juga ditemukan istilah aringgit yang berarti ‘petugas yang mengurus wayang kulit’ (Bandem, 1996: 22). Di samping dalam bentuk wayang kulit, dalam bahasa Jawa Kuna juga dikenal istilah wayang wwang yang berarti wayang wong atau wayang orang. Istilah wayang wwang ditemukan pada prasasti Wilmalasrama (abad X). Diperkirakan wayang wwang tersebut berbentuk drama tari topeng dengan membawakan cerita Mahabarata dan Ramayana. Bahkan dalam prasasti Jaha (tahun 840 M) pertunjukan drama tari topeng dengan cerita dari Mahabarata dan Ramayana telah ada dengan istilah atapukan. Istilah atapukan ini masih ditemukan dalam kitab Pararaton dari abad ke-16. Istilah lain dalam bahasa Jawa Kuna yang berarti drama tari topeng adalah raket (terdapat dalam kitab Negarakertagama, dari abad ke-14) dan patapelan (terdapat dalam Kidung Sunda, dari abad ke-16). Schrieke dan Pigeaud berpendapat bahwa raket adalah drama tari topeng yang membawakan cerita Panji. Dalam perkembangannya drama tari topeng tersebut berubah menjadi drama tari tanpa topeng, seperti di Bali dikenal dengan sebutan gambuh (Soedarsono, dalam Ben Soeharto, dkk., 1999: x). Dalam prasasti Trowulan-Mojokerto yang bertahun 1358 M. disebutkan bahwa 140 raja Hayam Wuruk dari Majapahit berperan sebagai badut dalam teater topeng (Bandem, 1996: 22). Wayang dari Jawa Kuna tersebut terus berkembang baik dari segi bentuk bonekanya maupun ceritanya. Tentu saja perkembangan tersebut juga diikuti perkembangan berbagai bentuk dan pola-pola dramatiknya. Sesudah kerajaan Majapahit runtuh akhir abad ke-15 pertunjukan teater topeng mengalami kemunduran drastis. Baru setelah berkembang kerajaan-kerajaan Islam di Jawa Tengah, seperti Demak, Pajang, dan Mataram, teater istana dapat berkembang kembali. Invasi kekuasaan Barat di Jawa Tengah dan dengan jatuhnya Mataram ke tangan Belanda tahun 1743 memberi prospek yang amat cerah untuk perkembangan kesenian drama di Jawa Tengah. Hal ini dimungkinkan karena pengaruh budaya teater Barat dapat sebagai hiburan sekaligus sebagai alat propaganda kepentingan tertentu. Setelah pecahnya Mataram menjadi dua, yakni Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta, teater memperoleh perhatian yang besar pada masingmasing kerajaan. Pada saat itu antara lain muncul dan berkembang Wayang Wong dan Langendriyan. Wayang Wong tampil dengan tari-tarian dan dialog berbahasa Jawa prosa dan membawakan cerita dari Mahabarata dan Ramayana. Sedang Langendriyan tampil dengan tarian jongkok, dengan dialog berupa nyanyian (tembang Jawa), membawakan cerita Damarwulan (Bandem, 1996: 24). Di Yogyakarta, kemudian juga muncul Langen Mandrawanara, yang juga tampil dengan tarian jongkok dan berdialog dengan tembang macapat. Langen mandrawanara membawakan cerita dari Ramayana dan Babad Lokapala. Bila Wayang Wong di Yogyakarta diciptakan oleh Sultan Hamengku Buwana I, Wayang Wong di Surakarta diciptakan oleh Adipati Arya Mangkunegara I di Mangkunegaran. Langendriyan diciptakan oleh Raden Tumenggung Purwadiningrat pada tahun 1876. Sedang Langen mandrawanara diciptakan pada tahun 1890 oleh seorang Patih di Kasultanan Yogyakarta yang bernama Kanjeng Pangeran Adipati Arya Danureja VII (Soedarsono, 1999: xii). Sejak adanya pengaruh drama Barat dan cara pemanggungannya, pada permulaan abad 20 timbul bentuk drama baru di Indonesia, yaitu komedi 141 stambul, tonil, opera, wayang wong, kethoprak, ludruk, dsb. Pementasan dramadrama ini juga belum menggunakan naskah (Sumardjo, 1992: 255) Dari pola dramatik wayang kemudian pada sekitar tahun 1908 muncul dan berkembang drama Ketoprak. Sebagaimana Langendriyan dan Langen mandrawanara, Ketoprak muncul sebagai seni drama yang berkembang dari rakyat jelata di luar istana. Cerita Ketoprak pada mulanya dibuat berdasarkan cerita kehidupan sehari-hari para petani di desa. Kemudian mendapat pengaruh cerita dari berbagai sumber, yakni dari cerita-cerita yang telah berkembang di Jawa pada saat itu, kemudian juga termasuk cerita-cerita yang berasal dari luar, antara lain cerita Seribu Satu Malam, Sam Pek Eng Tai, dan cerita-cerita sejarah tradisional dari sumber yang tertulis dalam bentuk babad. Di Jawa bagian timur, sejarah drama panggung sedikit berbeda dengan di Jawa tengahan. Ludruk yang merupakan hiburan masyarakat Jawa bagian timur sudah berkembang jauh sebelum kethoprak, bahkan sudah ada sejak abad XII. Ludruk muncul dari bentuk pertunjukan atraktif, jadi nilai dramatisnya sangat minim, yakni atraksi kekebalan tubuh dan bela diri. Baru pada awal abad XX, muncul ludruk Besutan dengan cerita tentang Pak Besut yang mencari istrinya, Asmunah, hingga bertemu di Jombang. Bila kethoprak tradisional banyak berkembang dengan cerita-cerita dari babad yang notabene bersifat istana centris, ludruk lebih banyak menggunakan cerita sehari-hari. Mungkin hal ini berhubungan dengan pengaruh pamor atau kharisma istana Jawa Mataram (Yogyakarta dan Surakarta) yang masih kuat untuk DIY dan Jawa Tengah, tetapi pengaruh istana itu yang sudah lemah untuk Jawa Timur. Setelah masuknya pengaruh modernisme dari Barat, melalui sarana audio atau radio, drama Jawa juga mulai berkembang sebagai drama radio. Drama di radio ini sesuai dengan jenisnya masing-masing. Drama Jawa pendek yang bersifat komedi yang disebut dhagelan, semula merupakan hasil tugas dari abdi dalem oceh-ocehan dari gusti Hangabehi, putra Hamengkubuwana VIII. Di depan ndalem Ngabean milik gusti hangabehi terdapat pemancar radio milik Belanda yang bernama radio MAVRO. Salah satu siaran rutinnya adalah uyon-uyon. Atas prakarsa pangeran Hangabehi, maka lawakan dari abdi dalem oceh-ocehan itu dimasukkan sebagai siaran selingan uyon-uyon. Lawakan selingan itulah yang 142 kemudian diberi nama dhagelan dan akhirnya disebut dhagelan Mataram (Poedjosoedarmo, dkk., 2000: 222). Kethoprak di radio mulai disiarkan pada tahun 1935 dipelopori oleh grup Kridho Raharjo pimpinan almarhum Ki Tjokrojio, tokoh kethoprak legendaris (Widayat, dalam Purwaraharja, ed. 1997: 43). Sedang program sandiwara radio berbahasa daerah (Jawa) mulai disiarkan di RRI Stasiun Yogyakarta sekitar tahun 1963/ 1964, dengan sutradara Soemardjana, dengan pemain-pemain antara lain Umar Khayam, Habib Bari, Bakdi Soemanto, Hastin Atas Asih. Program ini disiarkan dua kali per minggu, yakni hari Minggu dan Kamis, dengan tujuan: 1) memperkenalkan nilai-nilai kerokhanian dan moral yang tinggi dari masyarakat suatu jaman, 2) penanaman keyakinan dan kepercayaan bahwa setiap sifat kejahatan dapat dilenyapkan oleh kebenaran, kejujuran, dan keluhuran budi, 3) mensinyalir sifat dan gejala yang membahayakan masyarakat atau menghambat kemajuan bangsa dan menunjukkan jalan bagaimana sifat dan gejala itu dapat diberantas (Onong U. Effendy : 99) judul dan tahun blm? e. Fungsi dan Tujuan Drama Jawa Secara garis besar fungsi drama Jawa tidak jauh berbeda dengan funsi jenis drama pada umumnya, bahkan juga tidak jauh berbeda dengan funsi sastra pada umumnya. Innis (1967: 67-68) mencatat bahwa tujuan menulis drama antara lain: (1) menghibur agar orang dapat tertawa terpinglkal-pingkal dan senang hatinya, (2) memberikan informasi kepada orang tentang fenomena fisik, obyek-obyek, cuaca, dunia binatang, siang dan malam, khayalan, dan (3) memberikan tuntunan tentang tingkah laku dan perkenbangan pola tingkah laku. Sedang Loren E. Taylor ( 1981: 4-5) mencatat nilai-nilai yang terdapat dalam drama, yakni antara lain: (1) memperluas budaya, (2) memperkembangkan apresiasi terhadap sesuatu yang indah, (3) memperkembangkan kesedapan sikap, (4) mendorong imajinasi, (5) menyediakan rekreasi sehat, (6) memberikan kesempatan untuk ekspresi pribadi, (7) mengembangkan cita rasa, (8) mengembangkan kerja sama, (9) mengembangkan rasa percaya diri sendiri, (10) 143 mengembangkan rasa tanggung jawab pribadi, (11) mengembangkan kemampuan untuk menerima kritik, (12) menstimulasi otak, (13) menambah kemampuan untuk menafsirkan kehidupan, (14) mengajarkan sikap-sikap yang baik, (15) mengembangkan daya pikir yang cepat, (16) mengembangkan sikap jujur, (17) mengembangkan pengorbanan diri, (18) mengembangkan inisiatif, (19) melatih penonton bersikap dewasa, (20) dan sebagainya. Adapun mengenai fungsi drama Jawa, setidak-tidaknya ada beberapa pengamat yang menuliskan sebagai berikut. Menurut Saptono (Kompas, 3 Agustus 1997) drama Jawa dapat menyehatkan imajinasi. Menurut Dumairy (Kedaulatan Rakyat, 29 Juni 1997) drama Jawa juga dapat digunakan sebagai wahana penanaman jiwa wiraswasta. Menurut Kak We Es Ibnu say (Suara Pembaruan, 26 Oktober 1997) drama Jawa mampu mengembangkan seluruh daya pikir yang kritis, imajinatif, dan kreatif. Drama Jawa juga dapat membuat orang memiliki sikap solidaritas, saling hormat-menghormati dan saling menghargai. Sedang menurut Sopingi (1998:1) drama Jawa mampu membentuk budi pekerti. Hal ini sesuai dengan yang termuat dalam Republika (21 Desember 1997: 22) bahwa drama Jawa mengandung pesan moral. Kak Seto (1995: 3) juga mencatat bahwa bila di kampus seorang dosen mendrama Jawa atau mahasiswa membaca dan mengapresiasi drama Jawa, tanpa disadari mereka telah menyerap beberapa sifat positif, seperti: keberanian, kejujuran, kehormatan diri, memiliki cita-cita, rasa cinta tanah air, kemanusiaan, menyayangi binatang, membedakan hal yang baik dan hal yang buruk, dan sebagainya. f. Klasifikasi Drama Jawa 1). Menurut Sarana Tempat Pementasannya Menurut sarana tempat pementasannya, drama dapat dibedakan sebagai berikut. a. Drama Panggung: dengan layar setting dan tanpa layar setting b. Dengan audio atau audio-visual: di radio, tape recorder atau TV, VCD, dan DVD 144 Dalam hal drama panggung, yakni drama yang dipentaskan dipanggung, dapat dibedakan lagi dengan drama hiburan gratis, drama tanggapan, dan drama tobong, dan drama karena lomba. Drama hiburan gratis biasanya terjadi pada even-even acara nasional, seperti acara peringatan hari kemerdekaan RI. Pementasan drama seperti ini tidak terlalu menekankan pada kualitas. Drama tanggapan adalah drama yang ditanggap orang yang sedang memiliki hajatan. Drama tobong adalah drama yang pementasannya dengan membuat rumah tobong agar masyarakat yang mau menonton harus memasuki rumah tobong dengan membayar tiket dengan kelas dan sejumlah uang yang sudah ditentukan rombongan pemain drama. Baik drama tanggapan maupun drama tobong telah memperhitungkan kualitas demi komersial keberterimaan masyarakat (tingkat laku). Drama karena lomba, adalah drama yang pementasannya dikarenakan adanya lomba pementasan drama. Drama karena lomba sangat menekankan kualitas karena tujuannya yakni untuk memenangkan lomba atau sayembara. Hingga saat ini di Jawa, drama yang bersifat komersial kebanyakan baru drama-drama yang dapat dikategorikan sebagai drama tradisional, atau semi tradisional, yakni wayang purwa, kethoprak, dhagelan, ludruk, dan sebagainya. Drama ini sebagian besar tanpa dengan naskah, dan sebagiannya menggunakan naskah pokok yang tidak lengkap. Dalam hal drama yang bermedia audio sedikit berbeda dengan yang bermedia audio visual, yakni dalam bentuk penulisannya. Hal ini dikarenakan alasan praktis dan fungsi masing-masing media yang memang berbeda karakteristiknya. Dalam drama audio di radio, berbagai teks samping akan dibaca agar pendengar dapat menangkap alur cerita dan setting waktu, tempat dan suasana dalam cerita. Sedang dalam audio visual (TV, VCD dan DVD), teks samping tidak dibaca, tetapi divisualisasikan, sehingga memerlukan teknis khusus. 2). Menurut Gaya Pementasannya Menurut gaya pementasannya drama Jawa dapat dibedakan sebagai berikut. 145 a. Drama tradisional b. Drama modern Di atas telah disinggung bahwa klasifikasi ini terutama didasarkan oleh ada dan tidaknya teks tertulis sebagai dasar pementasan. Drama tradisional adalah drama yang dalam pementasannya belum menggunakan teks tertulis atau naskah dan mengandalkan profesionalisme dan improfissasi langsung dari pemainnya di panggung. Sedang dalam drama modern menekankan penulisan perencanaan yang matang untuk dipakai sebagai pedoman pementasannya (naskah). Penghayatan pemain di dasarkan atas pembacaan naskah yang disediakan. Di atas juga telah disinggung bahwa dalam drama Jawa terdapat tradisi menulis naskah pedoman secara tidak lengkap, yakni hanya dituliskan pokokpokok adegannya dan inti isi pembicaraan tiap adegan. Dalam tradisi wayang purwa naskah seperti itu disebut Pakem balungan. 3). Menurut Masyarakat Pendukungnya Menurut masyarakat pendukungnya drama Jawa dapat dibagi menjadi sebagai berikut. a. Drama rakyat (kesenian rakyat) b. Drama istana (kesenian istana) Dalam sejarah drama Jawa, terutama jenis drama tradisional, terdapat drama istana, yakni drama yang muncul dan hidupnya berada dalam lingkungan istana saja, tetapi juga terdapat jenis drama rakyat, yakni yang memang muncul dari rakyat jelata dan berkembang di pedesaan. Yang termasuk drama istana antara lain wayang wong, meskipun pada akhirnya juga berkembang menjadi drama rakyat. Drama rakyat contohnya adalah kethoprak, yang pada mulanya hanya bercerita tentang petani di sawah yang dikirim makan oleh isterinya. Pada umumnya drama istana memiliki ciri-ciri bentuk yang rumit dan halus dan dengan aturan yang relatif ketat. Sebagai contoh adalah tarian Jawa klasik yang harus dikuasai oleh para pemain wayang wong serta segala aturan tampil dan dialognya. Sebaliknya, drama rakyat relatif lebih sederhana, relatif kasar dan lebih bebas. 146 4). Menurut Sifat Isi Ceritanya Menurut sifat isi ceritanya drama Jawa dapat dibagi menjadi sebagai berikut. a. Komedi (dhagelan) b.Tragedi c. Melodrama Dalam drama Jawa, sesungguhnya klasifikasi tersebut tidak begitu ditekankan, karena filosofi budaya Jawa yang mendasarinya tidak banyak mendukung. Seperti telah disinggung di depan, bahwa konsep filosofis sakmadya yang berarti ‘sedang-sedang saja’ telah mempengaruhi berbagai segi kehidupan termasuk dalam berkesenian. Dalam drama Jawa, cerita-cerita yang paling tragis pun, misalnya dalam lakon Sumba Sebit, yang menceritakan kematian tokoh Sumba, anak Kresna, dengan cara di robek-robek tubuhnya, pun diisi pula dengan senda gurau para abdi atau panakawan dalam bentuk lawakan. Dengan demikian dalam drama Jawa tidak banyak cerita tragedi yang sesungguhnya. Sebaliknya, drama dhagelan yang bersifat komedi sering diwarnai dengan permasalahan kehidupan yang kadang kala memerlukan jalan keluar yang tidak gampang. Pada akhir-akhir ini banyak permasalahan sosial dan politik yang dikemas dalam bentuk komedi atau dhagelan. 5). Menurut Pelaku Cerita atau Boneka yang Dimainkannya Menurut pelaku cerita atau boneka yang dimainkannya, drama Jawa dapat dibagi menjadi sebagai berikut. a. Orang (wayang wong, kethoprak, ludruk, langendriya(n), drama tari, dsb) b. Golek kayu (wayang golek/ wayang Thengul) c. Kulit/ Kardus (wayang kulit/ kardus) d. Gambar pada layar (wayang beber) e. Bahan lain yang berfungsi sebagai mainan (misalnya wayang rumput) Pada wayang wong, kethoprak, ludruk, langendriyan, drama tari dan sebagainya, diperlukan orang sebagai pelaku tokoh-tokoh cerita. Sedang pada wayang golek, wayang kulit, wayang beber dan sebagainya, tokoh-tokoh cerita cukup diwakili oleh seorang dalang. 147 g. Tradisi Lisan dan Tulisan dalam Drama Jawa Di Jawa tradisi penulisan naskah sebenarnya telah ditemukan buktibuktinya sejak digunakannya bahasa Jawa Kuna, terutama dalam Lontar. Pada saat itu juga telah tercatat adanya bentuk semacam teater yang mengambil cerita dari Ramayana dan Mahabharata, yang mungkin lebih menyerupai wayang wong. Namun demikian tidak ditemukan tradisi penulisan naskah yang secara khusus ditujukan untuk pementasan atau teater. Tradisi pertunjukan di Jawa memang tidak mengharuskan penulisan khusus naskah lakonnya. Tradisi penulisan naskah terus berlangsung hingga pada saat digunakannya kertas dalam bahasa Jawa Baru. Ribuan naskah carik (tulisan tangan) berhuruf Jawa dapat ditemukan di berbagai perpustakaan, baik di Jawa maupun yang sudah dibawa ke luar negeri. Pada abad 18 dan 19, yakni pada masa merebaknya penulisan kembali naskah-naskah lama dan penerjemahan naskah-naskah berbahasa Jawa Kuna ke dalam bahasa Jawa Baru, banyak ditulis naskah-naskah cerita yang bersumber dari Ramayana dan Mahabharata. Di antara naskah yang disalin, banyak disalin dalam bentuk prosa. Namun Behrend, dengan mengacu pendapat Pigeaud, juga mencatat bahwa pada abad 18 dan 19 itu banyak juga ditulis naskah-naskah wayang yang berbentuk pakem (Behrend, Jakarta: Jambatan, 1990). Yang dimaksud pakem di sini adalah naskah yang sengaja ditulis dengan tujuan untuk pedoman pementasan teater, terutama wayang purwa. Dengan demikian ada kemungkinan bahwa tradisi penulisan drama Jawa dimulai pada saat itu. Meskipun demikian pada dasarnya tradisi pementasan wayang purwa merupakan tradisi lisan yang ditularkan oleh dalang kepada generasi dalang selanjutnya melalui pementasan. Oleh karena itu tradisi penulisan pakem wayang pun tidak berjalan lama. Bahkan kecenderungan yang terjadi hanya berupa tradisi menyalin atau menulis kembali teks-teks yang telah ada, baik dari teks tertulis maupun lisan. Semasa hidup Sultan Hamengkubuwana VIII, menurut keterangan dari para empu tari beliau, beliau menulis sendiri naskah-naskah lakon wayang wong gaya Yogyakarta dan dipentaskan hingga berhari-hari pada waktu siang hari. 148 Konon rekor penontonnya dalam waktu empat hari mencapai 30.000 penonton (Atmadipurwa, 1996: 73) Pada perkembangannya tradisi penulisan lakon untuk wayang purwa ternyata juga tidak diikuti oleh tradisi penulisan lakon pada bentuk drama selain wayang, terutama drama rakyat yang dipentaskan di panggung-panggung rakyat, seperti kethoprak di Jawa Tengah dan DIY atau Ludruk di Jawa Timur. Hal ini mungkin terjadi karena tradisi penulisan drama Jawa tidak mendapat sorotan serius dari para penulis profesional. Atau sebaliknya, para pecinta drama, pemain dan sutradara drama Jawa tidak terbiasa dengan tradisi kepenulisan. Dengan demikian tradisi pementasan drama Jawa pada umumnya juga merupakan tradisi lisan, yang ditularkan dari pementasan ke pementasan. Berbagai perkembangan dan perbaikan dari pementasan sebelumnya merupakan tindakan sesaat pada waktu pentas yang dikenal dengan istilah improvisasi. Tentu saja hal tersebut berpengaruh pada laju perkembangan drama yang bersangkutan, sehingga konvensi yang ada pada tradisi itu lebih menentukan dari improvisasi atau inovasi yang muncul. Tidak mustahil bila sampai saat ini, dibanding jenis prosa dan puisi, tidak banyak ditemukan naskah-naskah tertulis yang bersifat pembaharuan. Naskah-naskah drama wayang purwa, yang relatif banyak ditemukan di perpustakaan-perpustakaan pun, lebih mencerminkan hasil dari tradisi penyalinan teks, baik dari tradisi tulis ke tulis atau dari lisan ke tulis. Lakon-lakon carangan yang bermunculan, lebih banyak muncul secara langsung dalam pementasan terlebih dulu dari pada ditulis dulu. Sedikit berbeda dengan kondisi di atas, tradisi modern dalam radio dan TV, menuntut kejelasan dan kepastian perencanaan, mulai dari misi dan visi hingga yang bersifat teknis seperti durasi waktu yang diperlukan, cara pengambilan suara, cara pengambilan gambar, dsb. Dengan demikian menuntut adanya tradisi tulis secara penuh. Dengan kata lain, lakon-lakon drama radio, apalagi TV, dituntut untuk ditulis terlebih dulu. Hal ini diperlukan demi pertanggungjawaban teknis maupun isi. Durasi yang dijatahkan sudah tertentu, visi dan misinya juga ditentukan, sehingga persiapannya sudah harus matang dan bisa diketahui secara detail sebelum disiarkan. 149 Sandiwara Keluarga Yogya karya Soemardjono yang disiarkan RRI Nusantara II Yogyakarta telah menggunakan tradisi naskah. Konon kethoprak RRI juga dirintis oleh Soemardjono dalam hal penggunaan naskah. Pada dekade 1970, ketika kethoprak muncul di TV yang diprakarsai oleh TVRI Yogyakarta, format penulisan naskahnya dipaksa dengan format media audio visual. Namun pada awalnya format sinematografinya belum menyentuh banyak hal. Namun pada cerita Kidung Perenging Dieng (1973) benar-benar menjadikan tontonan yang “meledak”. Sejak saat itu kethoprak TV diusahakan menggunakan format sinetron/ film sehingga lebih menarik (Atmadipurwa, 1996: 76). Dengan demikian teks-teks drama radio dan TV banyak meninggalkan bekas berupa tulisan. Tradisi penulisan drama, baik yang direncanakan dengan media elektronika seperti radio, TV dll, maupun yang direncanakan dengan media panggung bebas mengalami perkembangan secara lebih intensif, tentu saja setelah masa kemerdekaan. Hal ini antara lain disebabkan oleh kondisi sosial politik yang lebih bebas. Kondisi tersebut ditunjang dengan berbagai bentuk pembinaan yang di antaranya dengan diselenggarakannya berbagai lomba. Lomba pementasan kethoprak di Yogyakarta, misalnya, sebagiannya juga mewajibkan untuk menulis naskah lakonnya dulu. Demikian pula perintisan kembali dan pembinaan grup-grup kethoprak di daerah-daerah, sebagiannya juga dilalui dengan penulisan naskah lakonnya. Menurut Suripan Sadi Hoetomo (1993: 60-61) perbedaan drama atau sandiwara tradisional dengan sandiwara modern yaitu dalam drama modern telah dikenal naskah yang menuntun para aktor (pemain) untuk mempelajari dialogdialognya sebelum dipentaskan, sehingga mereka tak lagi megucapkan dialogdialog secara improfisasi. Pada saat ini kehidupan drama di Jawa, dari segi naskahnya, bisa diklasifikasikan menjadi tiga, yakni pertunjukan full improfisasi, semi naskah, dan naskah full play. Yang lisan, spontan dan improvisasi sepenuhnya, masih banyak dilakukan oleh grup-grup kesenian tradisional. Ada juga yang menggunakan naskah tetapi hanya diacu jalan cerita pokoknya saja. Sedang yang 150 di radio dan TV tentu saja menggunakan naskah full play (Bdk. Atmadipurwa, 1996: 75). Dalam hubungannya dengan drama yang modern dan yang tradisional, harus dicatat secara khusus mengenai jenis langendriya atau langendriyan. Langendriyan dalam berbagai atribut dan sarana pentasnya termasuk dalam drama tradisional. Namun demikian, drama ini telah mengandung unsur-unsur modern, yakni menggunakan teks naskah lengkap sebagai acuan pementasannya. Dialog yang dipergunakan berupa tembang macapat, sehingga dapat dikategorikan sebagai opera berbahasa Jawa. Soenarto Timoer, 1980 (via Hutomo, 1983: 61) mencatat adanya teks drama langendriyan yang terkenal yakni Langendriyan Mandraswara (diterbitkan oleh Balai Pustaka) karya R.M. Arya Tandakusuma. Teks ini terkenal karena selain ikatan tembangnya indah dan bagus, pengisahannya pun ringkas, padat, dan sederhana sehingga mudah diikuti. Perkembangan penulisan naskah drama Jawa modern juga dilalui dengan adanya berbagai lomba penulisan naskah drama. Suripan Sadi Hutomo (1993: 59) mencatat bahwa drama Jawa, sebagai sastra tulis belum muncul secara mencokok dalam sastra Jawa modern. Namun hal itu berubah semenjak Pengembangan Kesenian Jawa Tengah (PKJT) menyelenggarakan sayembara penulisan naskah drama berbahasa Jawa pada tahun 1979 dan 1980. Sayembara itu kemudian disusul dengan pementasan-pementasan drama berbahasa Jawa di berbagai tempat di Jawa Tengah. h. Jenis-jenis Drama Jawa 1). Wayang Purwa Kata wayang dalam bahasa Jawa berarti “bayangan” atau “bayangbayang”. Wayang purwa adalah salah satu jenis seni drama Jawa, yang menggunakan boneka wayang kulit sebagai media penyampaian cerita dramatiknya. Bayangan boneka wayang kulit itu dapat dilihat dari balik kelir atau layar. Kata “purwa”, menurut G.A.Y. Hazeu, berasal dari bahasa Sansekerta “purwa” yang berarti ‘pertama’ atau ’yang terdahulu’. Sedang menurut Van der Tuuk, berasal dari kata “parwa”, namun telah dikacaukan dengan kata “purwa”. Ia dan Brandes membandingkan dengan penamaan wayang di Bali yang disebut 151 wayang parwa (prawa) (Mulyono, 1978: 5). Di antara jenis seni pertunjukan wayang, yang paling populer dan paling luas daerah persebarannya di kalangan masyarakat Jawa adalah wayang kulit atau wayang purwa itu. Jenis wayang ini telah berumur sangat tua dan telah mengalami perkembangan dari masa ke masa baik perkembangan bentuk boneka wayangnya, ceritanya, maupun teknik penggarapan pementasannya Pada era elektronik ini wayang purwa sering ditayangkan di media radio, TV, VCD atau DVD. (a). Para Pengamat dan Pendapatnya tentang Wayang Purwa Ir. Sri Mulyono dalam bukunya Wayang: Asal-usul, Filsafat dan Masa Depannya (1978), mengumpulkan berbagai pendapat yang menyatakan bahwa drama wayang telah ada sejak zaman Jawa Kuna, antara lain yang terdapat dalam prasasti Balitung (907 M) yang menuliskan “mawayang buat Hyang” dan adanya lakon “Bhimaya Kumara”. Sebelumnya, yakni pada prasasti Jaha (tahun 840 M) juga ditemukan istilah aringgit yang berarti ‘petugas yang mengurus wayang kulit’ (Bandem, 1996: 22). Para pengamat asing mulai memperhatikan wayang mulai awal abad ke19. Mereka menganggap wayang sebagai unsur penting dalam kebudayaan Jawa, yakni sebagai “copelling religious mythology”, yang menyatukan masyarakat Jawa secara menyeluruh, secara horizontal meliputi seluruh daerah geografi di Jawa, dan secara vertikal meliputi semua golongan masyarakat di Jawa (Anderson, 1965, via Koentjaraningrat, 1984: 288-289). Koentjaraningrat menolak anggapan yang digeneralisir tersebut. Dengan menyebutkan contohcontoh yang dikenalinya, Koentjaraningrat merasa lebih pas dengan menganggap bahwa wayang hanya sebagai suatu pertunjukan drama yang dinikmati oleh banyak orang Jawa, tetapi hanya sebagai suatu bentuk kesenian saja. Dengan menuliskan contoh banyak pengamat asing dan domestik, Koentjaraningrat (1984: 289) menyatakan bahwa wayang merupakan bentuk kesenian rakyat Jawa yang paling banyak dideskripsi dan dikaji. Wayang dalam hal ini adalah wayang dalam arti luas, tidak hanya wayang purwa. Namun demikian, dalam halaman selanjutnya juga dinyatakan bahwa ringgit (wayang) 152 purwa merupakan wayang yang paling terkenal yang tekniknya telah berubah dari kesenian rakyat menjadi kesenian kraton. (b). Asal-usul Wayang Purwa . Beberapa karangan para pakar Barat menitikberatkan pada asal dan umur wayang purwa. Asal-usul pertunjukan wayang purwa di Jawa masih belum jelas, walau beberapa sarjana berpendapat bahwa pertunjukan wayang purwa adalah asli ciptaan orang Jawa, bukan dari India dan bukan dari kebudayaan asing lainnya. W.H. Rassers dalam desertasinya De Pandji Roman (1922) mengembangkan teori bahwa wayang adalah sisa dari upacara inisiasi totem di Jaman prasejarah di Jawa. Dalang adalah sebagaimana pendeta dari upacara inisiasi itu. Pringgitan atau bagian dari rumah tempat pertunjukan diadakan, adalah tempat pria dalam inisiasi totem yang sifatnya keramat dan terlarang bagi wanita dan anak-anak. Namun pendapat tersebut ditentang oleh R.Ng. Poerbatjaraka, dengan menunjukkan bahwa pemisahan antara pria dan wanita dalam pertunjukan wayang bukanlah hal yang penting dalam pertunjukan itu (Koentjaraningrat, 1984: 291-292). Menurut Poensen kemungkinan yang paling mendekati kenyataan ialah bahwa pertunjukan wayang mula-mula lahir di Jawa dengan bantuan dan bimbingan orang Hindu. Sedang menurut Brandes, pada kenyataannya orang Hindu memiliki teater yang sama sekali berbeda dengan teater Jawa, dan hampir seluruh istilah teknis yang terdapat dalam pertunjukan wayang adalah khas Jawa, bukan sansekerta. Niemann juga berpendapat bahwa wayang tidak mungkin berasal dari Hindu. Hazeu, dengan menyitir beberapa pendapat pakar juga berkesimpulan bahwa wayang tidak berasal dari Hindu. Hazeu juga menelusuri beberapa kata yang berhubungan dengan teknik pementasan wayang, yakni kata wayang, kelir, blencong, kepyak, dhalang, kothak, dan cempala. Kata-kata tersebut merupakan kata asli Jawa. Namun demikian menurut Vert, baik dalam gamelan maupun wayang, ada pengaruh dari bangsa yang lebih besar yakni bangsa Hindu (Mulyono, 1978: 8-9). (c). Sumber-sumber Cerita Wayang Purwa 153 Pada prasasti Balitung telah disinggung adanya lakon Bimaya Kumara, tidak jelas bagaimana cerita itu. Namun saat ini yang dapat ditemukan dalam cerita wayang purwa, hampir semuanya berasal dari kisah-kisah Mahabharata dan Ramayana yang semula merupakan kitab suci Hindu. Bila diteliti lebih lanjut, sebenarnya telah banyak terjadi penyimpangan cerita lakon wayang dari sumber Mahabharata dan Ramayana aslinya, yang tampaknya memang gubahan orang Jawa, baik berasal dari kakawin, berupa kreasi dalang tertentu (sanggit) atau memang penciptaan lakon carangan. Pada masa Jawa Kuna disalin dan digubah cerita-cerita pewayangan, antara lain: Arjuna Wiwaha Kakawin, Bhomakawya Kakawin, Bharatayudha Kakawin, Hariwangsa Kakawin, Parthayadna Kakawin, Dewaruci Kakawin, Sudamala, dsb. Saat ini ditemukan beberapa buku yang diyakini sebagai sumber cerita wayang purwa, yakni: (1) Serat Pustaka Raja Purwa karya R.Ng. Ranggawarsita (gaya Surakarta). (2) Serat Padhalangan Ringgit Purwa karya K.G.P.A.A Mangkunegara VII (gaya Surakarta) (3) Serat Kandha atau Serat Purwakandha (gaya Yogyakarta) (4) Serat Pedhalangan Ringgit Purwa Pancakaki Klaten (gaya Yogyakarta) (5) Serat Babad Lokapala Sumber-sumber cerita tersebut oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai babon cerita wayang. Dewasa ini banyak ditulis lakon-lakon wayang, dan bila muncul cerita-cerita baru atau cerita yang menyimpang jauh dari sumbersumber tersebut, sering dianggap sebagai cerita atau lakon carangan. Pada akhir-akhir ini sebenarnya banyak sekali hasil karya sastra pewayangan yang mungkin juga dipergunakan oleh dalang tertentu sebagai sumber cerita pementasannya, baik berupa lakon pokok atau lakon carangan. Dari berbagai sumber cerita yang ada, dan dari segi bentuknya dapat diklasifikasikan sbb. 1) Cerita wayang dalam bentuk prosa yang ditulis sebagai roman panjang yang bersumber dari Ramayana atau Mahabarata, baik untuk tuntunan pertunjukan atau untuk bacaan. Misalnya Pustaka Raja Purwa, Serat Purwakandha, dsb. 154 2) Cerita wayang yang diambil dari bentuk lakon, masih tampak pembagian adegan-adegannya, ditulis dalam bentuk tembang, misalnya Serat Wahyu Makutha Rama (Sekar) karya Siswaharsaya, Serat Pakem Bima Bungkus karya M.Ng. Mangun Wijaya atau Serat Bima Bungkus karya Can Cu An, dsb. 3) Pakem jangkep atau pakem padhalangan jangkep wayang purwa, yang berisi tuntunan atau pedoman lengkap untuk pertunjukan wayang purwa dalam satu lakon. Pada bentuk ini berisi pembagian adegan, kandha, janturan, antawecana, gendhing dan sasmitaning gendhing, tokoh-tokoh wayang yang harus dipentaskan, dsb. secara lengkap. Misalnya Pakem Jangkep Lampahan Sumbadra Larung, Pakem Jangkep Lampahan Suryatmaja Maling, dsb. 4) Pakem balungan wayang purwa, yang berisi ringkasan atau kerangka pokok adegan-adegan lakon wayang sebagai tuntunan atau pedoman pertunjukan wayang purwa. Dalam satu buku biasanya berisi lebih dari satu lakon. Misalnya Serat Padhalangan Ringgit Purwa karya K.G.P.A.A. Mangkunegara VII. 5) Cerita bersambung wayang purwa, yang biasanya ditulis secara bersambung dalam beberapa terbitan majalah berbahasa Jawa. Biasanya bentuk ini ditulis dalam bentuk prosa dengan bahasa populer. 6) Bentuk banjaran, yang menekankan pada cerita biografi tokoh-tokoh wayang tertentu. Dengan kata lain alurnya dipusatkan pada satu tokoh. Misalnya Banjaran Karna, Banjaran Bisma, dan banjaran-banjaran tokoh lainnya. 7) Analisa atau kupasan tentang hal-ihwal wayang purwa. Dalam hubungannya dengan sumber induknya, yakni Ramayana dan Mahabharata, dalam wayang purwa tersebar tiga jenis lakon, yakni (1) lakon baku, (2) lakon carangan dan (3). lakon sempalan. Lakon baku, atau lakon pokok, yaitu lakon yang diangkat dari cerita induknya, yakni dari Ramayana atau Mahabharata. Lakon carangan adalah lakon karangan yang masih mengambil dari lakon baku tetapi sudah diberi cerita dan bentuk baru. Adapun lakon sempalan, yaitu lakon yang dikembangkan dari sebuah peristiwa yang termuat dalam Ramayana atau Mahabharata, tetapi sudah sangat jauh atau sama sekali terlepas dari lakon baku (bdk. Mertosedono, 1992: 75) 155 (d). Unsur-unsur Sastra Wayang Purwa dan Konvensi-konvensinya Berdasarkan pada beberapa penjelasan di atas tampak bahwa wayang purwa telah berumur panjang dan memiliki tradisinya sendiri. Wajarlah bila sastra wayang purwa memiliki berbagai konvensi yang sangat mengikat. (Wibisono, 1987: 8). Pada gilirannya berbagai konvensi yang ada akan tampak pada berbagai unsur sastra wayang. Oleh karena itu di bawah ini perlu dibicarakan unsur-unsur sastra wayang dan berbagai konvensinya. (1). Tema dalam Wayang Purwa Tema umum yang dijumpai dalam lakon wayang adalah melukiskan pertentangan antar pihak protagonis melawan pihak antagonis dengan akhir kemenangan di pihak protagonis. Cerita wayang purwa, baik siklus Mahabharata maupun Ramayana di Jawa berakhir dengan kemenangan pihak protagonis. Demikian pula penggalan-penggalan cerita yang berbentuk lakon untuk pertunjukan wayang purwa semalam, pada umumnya juga berakhir dengan kemenangan pihak protagonis. Namun, ada juga satu dua lakon yang berakhir tragis pada pagi hari, terutama pada lakon-lakon perang besar Bharatayuda, misalnya dalam gaya Yogyakarta dalam lakon Seta Gugur, Gatutkaca Gugur, Abimanyu Gugur, Paluhan, dsb. Tema-tema dalam lakon wayang sebenarnya dapat diklasifikasikan antara lain sebagai berikut. 1) Tema kelahiran, misalnya: lakon Bima Bungkus (Laire Bima), Laire Abimanyu, Laire Wisanggeni, Laire Gathutkaca, Laire Parikesit, dsb 2) Tema Pernikahan, atau tema alap-alapan, misalnya: lakon Alap-alapan Surtikanti (Suryatmaja Maling, yakni pernikahan Suryatmaja), Alap-alapan Drupadi (pernikahan Puntadewa), Rabine Gathutkaca, Parta Krama (pernikahan Arjuna dengan Wara Subadra), dsb. 3) Tema kematian, misalnya: lakon Gathutkaca Gugur, Ranjapan (Abimanyu Gugur), Bisma Gugur, Aswatama Lena, Somba Sebit (kematian Somba), dsb. 156 4) Tema Wahyu, misalnya: lakon Wahyu Makutharama, Tumurune Wahyu Manik Imandaya Godhong Pancawala, Wahyu Padmasana Manik, Wahyu Purba Sejati, dsb. 5) Tema hancurnya kerajaan tertentu, misalnya lakon Bedhahe Dwarawati (hancurnya kerajaan Dwarawati dengan rajanya Prabu Padmanaba, oleh Kresna), Bedhahe Amarta, menceritakan hancurnya negara Amarta milik para jin oleh para Pandawa (Babad Alas Mrentani). 6) Tema murca, yakni menceritakan pusaka atau tokoh tertentu yang hilang atau pergi meningglkan istana tanpa pamit. 7) Tema begawan atau pandita palsu, pada umumnya begawan itu terjadi dari sukma atau yitmane Dasamuka, Batara Guru atau Batari Durga yang hendak membunuh para Pandawa, atau dari raja raksasa, atau justru terjadi dari kerabat Pandawa atau Kresna yang hendak menyelamatkan Pandawa dari fitnah Korawa, misalnya: lakon Begawan Kilat Buwana, Begawan Suryandadari, dsb. 8) Tema membangun, yakni membangun taman, candi, istana dan sebagainya. Contohnya lakon Semar Mbangun Kahyangan, Mbangun Taman Maerakaca, Mbangun Candhi Saptarengga, Semar Mbangun Jatidhiri, dsb. 9) Tema jumenengan, yakni tentang penobatan raja tertentu. Misalnya Jumenengan Parikesit, Gathutkaca Madeg Ratu, dsb 10) Tema duta, yakni tentang perjalanan seorang utusan raja. Misalnya lakon Anoman Duta, Kresna Duta, Drupada duta, Anggada Duta, dsb 11) Tema ngenger, yakni tentang tokoh yang mengabdi pada raja tertentu. Misalnya Sumantri Ngenger, Trigangga Suwita, Wibisana Balik, dsb 12) Tema boyong, yakni tentang perpindahan tempat bagi tokoh-tokoh tertentu. Misalnya lakon Semar Boyong, Pandhawa Boyong, Sri Mulih, dsb 13) Tema takon bapa, yakni tentang tokoh-tokoh kesatria, atau panakawan yang menanyakan siapa sebenarnya ayahnya. Misalnya lakon Antasena Takon Bapa, Petruk Takon Bapa, Tirtanata Takon Bapa, atau anak-anak Arjuna yang mencari tahu siapa ayahnya, dsb. 14) Tema tentang surga, yakni tokoh-tokoh kesatria yang dengan bertapa, dsb., sehingga dapat naik ke kahyangan untuk menanyakan tentang surganya atau 157 surga bagi orang tuanya. Misalnya lakon Anoman Takon Swarga, Pandhawa Swarga, Pandhu Swarga, dsb. 15) Tema tentang pertalian Ramayana dengan Mahabharata. Misalnya lakon Semar Boyong, Rama Nitik, Rama Nitis, Wahyu Makutharama, dsb. 16) Tema larung, yakni tokoh tertentu yang dibuang, misalnya lakon Sembadra Larung 17) Tema sesaji, yakni sesaji tertentu untuk memenuhi persyaratan tertentu. Misalnya lakon Sesaji Rajasuya. 18) Tema perjudian, misalnya lakon Pandhawa Dhadhu. 19) Tema banjaran, yakni tema yang menekankan biografi tokoh tertentu. Misalnya lakon Banjaran Karna, Banjaran Bima, Banjaran Gathutkaca, dsb. 20) DSb. (2). Alur atau Plot dalam Lakon Wayang Purwa Menurut Becker (1971: 220) Plot wayang disusun oleh peristiwa yang bersifat koinsidensi atau kebetulan. Dalam wayang sesuatu kebetulan memotivasi tindakan-tindakan. Wayang sangat sarat dengan simbol. Plot wayang terdiri dari tiga bagian utama yang masing-masing ditandai dengan suatu rentang titinada tertentu yang disebut pathet, yaitu pathet nem, pathet sanga, dan pathet manyura. Setiap pathet terdiri dari adegan utama yaitu jejer, adegan, dan perang. Setiap adegan utama mempunyai tiga unsur: janturan, gambaran tentang tindakan sebelumnya, ginem, serta sabetan. Plot wayang berjalan memutar seperti spiral. Pada umumnya karya sastra pedalangan atau lakon wayang purwa terikat oleh urut-urutan adegan secara konvensional. Urutan adegan dalam tradisi pedalangan Surakarta, misalnya, selalu diawali dengan jejer, disusul adegan gapuran, kedhatonan, paseban jawi, sabrangan, perang gagal, adegan pertapan, perang kembang, sampak tanggung, adegan manyura, perang brubuh, dan tancep kayon (Wibisono, 1987: 11). Urutan adegan gaya Surakarta yang lebih terinci dapat dirumuskan sebagai berikut (bdk. Sri Mulyono 1979: 111-113). 1. Periode pathet nem, dibagi menjadi 6 adegan (jejeran): 158 a. Jejeran raja yang dilanjutkan dengan kedhatonan, yaitu setelah selesai bersidang, raja disambut permaisuri untuk bersantap bersama. b. Adegan Paseban Jawi, yakni patih mewartakan hasil sidang kepada prajurit c. Adegan jaranan (pasukan binatang) d. Adegan Perang ampyak (menghadapi rintangan diperjalanan) e. Adegan sabrangan, yaitu adegan raksasa dari negeri lain f. Perang gagal, yaitu perang yang belum diakhiri dengan kemenangan dan kekalahan, atau berpapasan saja, atau mencari jalan lain 2. Periode pathet sanga dibagi menjadi tiga adegan: a. Adegan bambangan, yakni seorang kesatria berada di tengah hutan atau menghadap seorang pendeta b. Perang kembang, yakni perang antara raksasa melawan kesatria yang diikuti panakawan c. Adegan sintren, yaitu adegan kesatria yang sudah menetapkan pilihannya dalam menempuh jalan hidup 3. Periode pathet manyura, dibagi menjadi tiga adegan: a. Jejer manyura. Dalam adegan ini tokoh utamanya sudah menetapkan tujuan hidupnya, sudah dekat dengan yang dicita-citakan b. Perang brubuh, yakni adegan perang yang berakhir dengan kemenangan dan banyak korban c. Tancep kayon, yakni setelah tarian Bima atau Bayu, gunungan atau kayon ditancapkan di tengah kelir. Diakhiri dengan tarian golekan (boneka). Pembagian adegan gaya Surakarta tersebut sedikit berbeda dengan pembagian adegan gaya Yogyakarta. Bila disimak lebih jauh, perbedaan yang mendasar dalam pembagian adegan adalah sering munculnya tamu pada adegan pertama pada gaya Yogyakarta. Adanya tamu ini menyebabkan adegan kedua dan ketiga sedikit berbeda dengan gaya Surakarta. Di samping itu perbedaan yang lain adalah nama perang yang terjadi. Gaya Yogyakarta pada perang setelah jejer kedua disebut perang simpangan, perang setelah jejer ketiga disebut perang gagal. Hingga jejer ketiga dalam gaya Yogyakarta belum terjadi korban kematian dalam perang. Jejer ketiga diikuti adegan gara-gara. Kemudian jejer keempat, 159 dan seterusnya yang bila dilihat dari adegannya hampir sama (bdk. Mudjanattistomo, dkk. 1977, jilid I: 163-166). Contoh gaya Surakarta dan gaya Yogyakarta di atas, pada dasarnya hanya menegaskan bahwa alur dramatik wayang purwa yang menyangkut pembagian adegan-adegannya sangat terikat oleh konvensi yang berlaku pada masingmasing gaya yang ada. (3). Penokohan dalam Wayang Purwa Dalam hubungannya dengan penokohannya, wayang purwa juga memilliki konvensi yang sangat ketat. Seorang pengamat pewayangan mencatat bahwa aspek penokohan dalam wayang purwa, bahkan wayang pada umumnya, tidak menyimpang dari tradisi pedalangan. Keakraban penonton dengan tokohtokoh wayang dan karakternya begitu jelas. Baik dalang maupun penonton samasama mengenal konvensi dalam penokohan. Apabila terjadi penyimpangan pemerian oleh seorang dalang atau penulis tentang tokoh-tokoh tertentu, maka penonton atau pembaca akan memberikan reaksi sebagai tindak koreksi (Wibisono, 1987: 8). Konvensi penokohan dalam wayang tersebut sejalan dengan yang disimpulkan oleh Kuntowijoyo (1984: 127-129), yakni bahwa dalam sastra tradisional, tokoh tidak dibangun atas perkembangan logis dari kejiwaan pelakupelakunya, tetapi atas dasar perkembangan kejadian menurut penuturannya. Personalitas dibentuk untuk melancarkan kejadian, sedang kejadian-kejadian tidak mempengaruhi personalitas. Jadi para pelakunya tidak mengalami perkembangan kejiwaan, hanya mengalami perkembangan kejadian. Sastra di sini bertindak sebagai simbol dari pikiran kolektif, tanpa memberi kebebasan bagi perkembangan personalitas tokoh-tokohnya. Perwatakan tokoh-tokoh itu menurut pola sebuah karakter sosial, bukan karakter individual. Dengan perkataan lain, pikiran kolektif secara apriori telah menentukan sejumlah tipe ideal bagi tokoh-tokoh cerita. Penokohan dalam wayang, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi delapan kelompok, yakni kesatria, raksasa, dewata, pendeta atau brahmana, para abdi, jin atau setan, binatang yang dapat berbicara, dan benda- 160 benda yang dapat berbicara. Setiap kelompok ada yang bersifat baik dan ada yang bersifat Jahat. Namun demikian pada umumnya dapat dikatakan sebagai berikut (bdk. Deskripsi perwatakan yang dituliskan Brandon dan Magnis Suseno, dalam Suseno, 1982: 18-19). Pada kelompok kesatria, dalam siklus Mahabharata, pada umumnya kesatria Pandawa berwatak baik dan para Korawa sebaliknya. Pada siklus Ramayana, kelompok kesatrianya hanya ada beberapa, yakni keluarga Prabu Rama dan adik Rahwana yakni Wibisana, semuanya relatif berwatak baik. Pada kelompok raksasa, sebenarnya bisa dikelompokkan menjadi tiga, yakni sebagai berikut. 1) Raksasa yang mempunyai riwayat hidup sekali saja. 2) Raksasa yang sekedar dipergunakan untuk pengisi adegan. 3) Raksasa besar penjelmaan tokoh-tokoh tertentu. Raksasa pada kelompok pertama, pada umumnya hanya muncul pada lakon-lakon yang memang berhubungan dengan cerita hidupnya. Raksasa kelompok ini biasanya mati hanya pada lakon yang memang bercerita dalam hubungannya dengan kematiannya. Dengan kata lain ia memang hidup dan mati sekali saja. Pada umumnya raksasa memang digambarkan berwatak jahat, tetapi raksasa pada kelompok ini ada sebagian yang memiliki watak terpuji dari sisi tertentu. Kumbakarna, adik Rahwana, misalnya, dianggap terpuji karena nasionalismenya. Contoh lainnya Bagaspati, raksasa pendeta, ia rela menyerahkan nyawanya demi kebahagiaan Dewi Pujawati, anak puterinya, karena Narasoma, calon menantunya, tidak mau mempunyai mertua raksasa. Contoh lain lagi ialah Sukasrana, raksasa kecil adik Sumantri, yang sangat mengasihi kakaknya sehingga mau memindahkan taman Sriwedari demi kepentingan kakaknya. Namun Sukasrana harus mati juga demi kesenangan kakaknya, Sumantri. Masih ada lagi yang lainnya seperti kecintaan Kalabendana pada Gathutkaca, dsb. Raksasa pada kelompok kedua, ia hidup selalu dalam keadaan telah dewasa, tidak pernah diketahui kapan kelahirannya dan siapa orang tuanya. Boleh jadi ia muncul dalam cerita apapun dan mati dalam cerita apa pun juga dalam lakon yang sama, karena keberadaannya hanya dipakai sebagai pengisi 161 pada adegan tertentu saja. Nama tokoh-tokoh raksasa pada kelompok kedua ini dapat bermacam-macam, tetapi biasanya merupakan teman-teman raksasa yang bernama Cakil, atau Gendring Penjalin, yang berjumlah empat raksasa. Kelompok raksasa ini bagi orang Jawa sering dianggap sebagai simbolisasi dari empat nafsu manusia, sehingga perwatakannya memang jahat. Raksasa pada kelompok ketiga, yakni raksasa besar penjelmaan tokohtokoh tertentu. Raksasa besar ini biasanya, pada lakon yang sama, muncul dan kemudian kembali pada wujudnya yang sesungguhnya, yang dalam bahasa Jawa disebut badhar. Misalnya penjelmaan Sri Kresna, penjelmaan Puntadewa, dsb. Perwatakan raksasa ini sekaligus merupakan perwatakan tokoh aslinya. Pada kelompok dewata, pada umumnya berwatak baik. Namun demikian sebagian dewa sering kali diceritakan sebagai tokoh yang mudah menerima hasutan atau perminta-tolongan para Korawa, sehingga berwatak tidak baik. Bila para dewa berbuat jahat kepada para Pandawa biasanya yang mengalahkan adalah Semar, tokoh abdi Panakawan. Ada golongan dewa yang tidak pernah muncul dalam lakon wayang namun keberadaannya diakui sebagai penguasa tertinggi, yakni Sang Hyang Wenang. Para brahmana atau pendeta pada umumnya berwatak baik. Namun banyak juga lakon yang menceritakan tentang pendeta palsu, yang merupakan penjelmaan dari Dasamuka. Pendeta palsu ini selalu berwatak jahat. Dalam Mahabharata, pendeta Durna sering digambarkan baik, tetapi karena berada di pihak Korawa, sering juga digambarkan berwatak jahat. Tokoh para abdi bisa dikelompokkan menjadi empat, yakni para abdi pria tokoh protagonis, para abdi pria tokoh antagonis, para abdi wanita, dan abdi seorang Begawan atau Pendita. Abdi pria tokoh protagonis biasanya adalah para Panakawan, yakni Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong, yang biasanya digambarkan berwatak baik tetapi sering nakal (sembrana). Abdi pria tokoh antagonis biasanya Togog dan Mbilung atau Saraita, yang sering juga digambarkan berwatak jahat. Abdi wanita biasanya bernama Cangik (sebagai ibu atau biyung) dan Limbuk (sebagai anak perempuan atau dhenok), dapat sebagai abdi para tokoh baik maupun para tokoh jahat. Abdi wanita ini biasanya 162 berwatak baik. Abdi seorang Begawan biasanya seorang pria disebut Cantrik dan berwatak baik. Kelompok jin (dalam bahasa Jawa sering diucapkan jim, setan priprayangan) atau setan dalam wayang purwa muncul pada lakon-lakon tertentu saja. Namun demikian keberadaannya sangat penting. Sebagian besar jin atau setan difisualisasikan sebagai raksasa, namun ada juga sebagai kesatria dan lainlain. Ada dua kelompok jin dan setan dalam wayang purwa, yakni para jin setan yang termasuk dalam kelompok yang disebut Bajubarat dan para jin setan penghuni atau penguasa tempat-tempat tertentu. Bajubarat adalah sekelompok jin atau setan yang merupakan abdi Batari Durga. Mereka selalu muncul atas perintah atau ijin Batari Durga dan terutama sekali muncul pada lakon-lakon Mahabharata. Sedang jin dan setan penguasa tempat-tempat tertentu, antara lain muncul dalam lakon Babad Alas Mrentani, yakni para jin dan setan penghuni hutan Mrentani, antara lain para jin Pandawa yang kemudian menyatu pada diri para Pandawa. Pada kelompok binatang yang ada pada wayang purwa, ada beberapa binatang yang mempunyai biografinya, tetapi juga ada yang sekedar pengisi adegan. Sebagiannya lagi merupakan tokoh jadi-jadian. Tokoh-tokoh binatang dalam wayang purwa pada umumnya berwatak baik. Tokoh burung Jatayu dalam Ramayana berwatak baik. Tokoh-tokoh kera dalam Ramayana pada umumnya juga berwatak baik. Dalam wayang purwa terdapat benda-benda tertentu yang dapat berbicara, antara lain senjata-senjata pusaka para kesatria, gunung Maenaka, dan sebagainya. Mereka adalah tokoh-tokoh yang berbicara secara khusus dalam lakon-lakon tertentu saja. Di samping penggambaran secara umum seperti di atas, konvensi penokohan dalam wayang purwa telah memberikan perwatakan pada masingmasing tokoh utama secara khusus. Tokoh Werkudara, misalnya, mempunyai watak pemberani, gagah perkasa, jujur, dsb. Arjuna, berwatak halus, pemberani, dsb. Sengkuni, berwatak nakal, penghasut, curang, dsb. Dan sebagainya yang hampir semuanya bersifat stereotip atau tetap dari masa kanak-kanaknya hingga usia dewasanya. Tidak mengherankan bila dalam cerita kelahiran Bima, sejak 163 lahir Bima telah mengenakan berbagai pakaian pelengkapan yang melambangkan perwatakannya. (4) Latar dalam Drama Wayang Purwa Konvensi dalam wayang purwa dalam hubungannya dengan unsur latar cerita (setting), mencakup aspek ruang atau tempat, waktu, dan suasana. Pada dasarnya latar tempat dalam cerita wayang dapat dibagi sebagai berikut. 1) Tempat di Madyapada yakni di dunia ini. 2) Tempat di Kahyangan yakni tempat para dewa, dan 3) Di Lokantara, yakni tempat nyawa atau jiwa yang masih melayanglayang (nglambrang). Di Madyapada dapat terjadi (1) di dalam istana, (2) di keputren, (3) di paseban jawi, (4) di hutan, (5) di Blabar Kawat, yakni arena pertengkaran atau mengadu kesaktian, (6) di pertapaan, dsb. Pada masing-masing tempat itu dapat terjadi di atas bumi, di angkasa atau di langit yakni tempat para tokoh tertentu terbang, di dasar bumi (sajroning pratala), yakni tempat tokoh-tokoh tertentu amblas di bawah bumi, dan di dalam air atau samodera. Tokoh yang dapat terbang antara lain Gathutkaca dan Kresna. Tokoh yang dapat amblas di dasar bumi antara lain Antareja. Adapun tokoh yang dapat berada di dalam air antara lain Antareja, Antasena, Yuyurumpung, dsb. Dalam lakon apa pun masingmasing tempat tersebut digambarkan secara stereotip. Dalam hal latar tempat pada setiap pertunjukan, Menurut Becker (1971: 220), dibagi tiga: (l) latar pertemuan di dalam istana, pertapaan atau di tanah asing dan (2) latar di luar istana yaitu di hutan, di kereta, di pintu gerbang, serta (3) latar peperangan. Cara menunjukkan latar dalam wayang yaitu dengan janturan dalang yang biasanya ditunjukkan dalam jejer, adegan, perang (Becker, l971 : 220). Dalam aspek waktu, wayang purwa tidak pernah memberikan penjelasan waktu secara riil, kecuali hanya disebutkan jaman purwa atau jaman dulu kala. Namun demikian dalam hubungannya dengan para abdi, perbincangan para abdi (para Panakawan, Limbuk dan Cangik, Togog dan Mbilung atau para Cantrik di 164 pertapaan) dapat menggunakan latar waktu terkini dan dengan pembicaraan dalam hubungannya dengan masyarakat penontonnya. Dalam aspek suasana, terdapat penggambaran suasana alam atau suasana kejiwaan tokoh-tokohnya, yang dapat digambarkan secara realis atau bombastis. Suasana sedih dan gembira, dapat saja digambarkan secara realis. Namun suasana keindahan istana, dapat saja digambarkan secara bombastis, misalnya air selokan yang mengalir dari istana menebarkan bau harum hingga di pedesaan, dsb. Latar suasana dalam lakon atau pergelaran wayang dapat ditunjang dengan karakteristik isi suluk seorang dalang. Suluk adalah nyanyian atau lagu vokal yang diucapkan oleh seorang dalang (bdk. Soetandyo, 2002: 121). 2) Wayang Wong (a) Sejarah Singkat Wayang Wong Munculnya wayang wong menurut Padmosoekotjo, (tt, jilid II: 63) pada tahun 1910. Cerita yang dibawakan sama dengan cerita dalam wayang purwa, namun diringkas. Dalam wayang purwa biasanya runing time-nya sekitar 9 jam dan dalam wayang wong hanya sekitar 3 jam. Menurut KPA Kusumodilogo, dalam bukunya Sastramiruda (1930), wayang wong pertama kalinya dipertunjukkan pada tahun 1760. Pertunjukan ini mendapat tantangan yang hebat bahkan dalam desertasi G.A.J. Hazeu (1897) yang berjudul Bijdrage tot het Kennis van het Javaansche Tooneel, dengan perubahan-perubahan bentuk pertunjukan wayang tersebut diramalkan akan menjadikan orang dalam kesulitan, celaka atau timbul penyakit (Haryanto, 1988: 78). Dalam catatan Bandem, dkk (Bandem, dkk., 1996: 82) wayang wong adalah salah satu bentuk teter daerah Jawa yang memadukan tiga cabang kesenian, yakni tari, karawitan, dan drama. Wayang wong Jawa lahir pada pertengahan abad ke-18, di dua keraton, Kesultanan Yogyakarta dan istana Mangkunegaran Surakarta. Karenanya di Jawa masih bisa dilihat adanya dua gaya wayang wong, yakni gaya Yogyakarta dan gaya Surakarta. Wayang wong di Jawa sesungguhnya merupakan personifikasi dari wayang kulit (purwa). Kaitan keduanya masih bisa dilihat dari berbagai aspek, seperti sumber cerita, 165 penggolongan watak, tari dan iringan karawitan, dialog, peran dalang, tata pakaian, tata rias dan sebagainya. Semula wayang wong hidup dan berkembang di istana tetapi lama kelamaan berkembang juga di luar istana . (1) Wayang Wong Gaya Yogyakarta Wayang wong gaya Yogyakarta diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwana I, yang dikenal juga sebagai seniman kreatif dan pelindung kesenian. Adapun gaya Surakarta diciptakan di istana Mangkunegaran Surakarta oleh Sri Mangkunegara I. Dengan memperbandingkan wayang wong, parwa Bali dan relief candicandi di Jawa Timur, Prof. Dr. RM. Soedarsono berkesimpulan bahwa wayang wong Yogyakarta yang diciptakan oleh Hamengkubuwana I pada sekitar tahun 1758, merupakan bentuk pelestarian wayang wwang dari jaman Jawa Kuna. Prasasti tertua yang memuat berita tentang wayang wwang adalah prasasti Wilasrama berasal dari tahun 930 M (Soedarsono, ……). Di Yogyakarta, lakon wayang wong yang dipergelarkan pertama kali berjudul Gandawardaya yang bersumber dari Mahabharata. Baik di Yogyakarta maupun di Surakarta, wayang wong mengalami perkembangan pesat sekitar tahun 1940. Di Yogyakarta, yakni sekitar pemerintahan Sri Hamengku Buwana VIII (1921-1939) berhasil dipentaskan 15 lakon yang sebagian besar bersumber pada Mahabharata, yakni Jayasemedi, Sri Suwela, Somba Sebit, Suciptahening Mintaraga, Parta Krama, Srikandhi Maguru Manah, Sumbadra Pralaya, Jaya Pusaka, Semar Boyong, Rama Nitik, Rama Nitis, Pregiwa Pregiwati, Angkawijaya Krama, Pancawala Krama dan Pragola Murti. Pergelaran wayang wong di istana Yogyakarta dipergelarkan secara besar-besaran dan mewah. Lakon Jayasemedi, Sri Suwela (1923), Somba Sebit, dan Suciptahening Mintaraga (1925) dilaksanakan selama empat hari berturutturut dengan mengerahkan tak kurang dari 800 orang seniman. Pakaian tari yang semula sederhana dikembangkan secara mewah sesuai dengan pakaian wayang kulitnya. Lantai pentas (tratag bangsal kencana) seluas 40 X 7 M, yang semula terdiri atas tanah berlapis pasir tipis, diganti batu pualam. 166 Salah satu ciri wayang wong gaya Yogyakarta ialah dipergunakannya teks lengkap yang disebut Serat Kandha dan Serat Pocapan. Serat Kandha berisi cerita lengkap dengan petunjuk-petunjuk berbagai elemen pementasan, seperti gendhing-gendhing yang mengiringi adegan-adegannya, keluar dan masuknya penari, vokal yang mengiringi berbagai suasana, dan sebagainya. Teks ini dibaca keras dan khitmat oleh juru cerita yang disebut Pamaos Kandha. Sedang Serat Pocapan berisi dialog lengkap yang harus diucapkan oleh para penari. Meskipun teks ini diletakkan di samping Serat Kandha, tetapi tidak dibacakan. Pembaca Serat Pocapan hanya bertugas memeriksa hubungan antara cerita yang dibaca oleh Pamaos Kandha dengan dialog yang diucapkan oleh para penari. Pamaos Kandha dengan Pamaos Serat Pocapan duduk di deretan paling depan dari jajaran penabuh gamelan (di kraton Yogyakarta berada di bagian timur dari tempat pentas di Tratag Bangsal Kencana, yakni di Bangsal Kuncung) (Soedarsono,….) Karena ide dasarnya adalah wayang kulit (purwa), maka perkembangan di Yogyakarta juga mengacu ke sana. Sebelum dan setelah usai pertunjukan di tengah pertunjukan diletakkan sebuah gunungan atau kayon seperti pada wayang kulit (purwa). Ukuran pentas yang memanjang mengasosiasikan kelir pada wayang kulit. Pembagian para pelaku pada kotak kiri (yang kebanyakan berwatak jahat) dan kanan (yang kebanyakan berwatak baik), serta posisi miring para penari di atas pentas, mirip dengan simpingsn dan adegan pada wayang kulit. Antara tahun 1920-an dan 1930-an, di Yogyakarta ditambahkan dengan dekorasi realistis, yakni dengan pepohonan, tanaman, atau menirunya dengan bentuk bangunan berkerangka. Pada tahun 1918, didirikan perkumpulan Krida Beksa Wirama oleh Pangeran Suryadiningrat dan Pangeran Tejokusumo. Grup ini di luar istana sehingga wayang wong Yogyakarta mulai berkembang di luar istana. Setelah 1940 wayang wong makin jarang dipentaskan di istana Yogyakarta. Setelah kemerdekaan 1945 dengan menurunnya Krida Beksa Wirama, muncul sejumlah grup tari yang menaruh perhatian pada wayang wong, yakni Irama Citra, Paguyuban Katolik Cipta Budaya, Paguyuban Satya Budaya, Langen Kridha Budaya, dsb. Pada tanggal 17 Agustus 1950, istana Yogyakarta diwakili oleh Kawedanan Hageng Punakawan Kridha Mardawa (lembaga Kraton di bidang 167 kebudayaan) kembali mendirikan organisasi tari bernama Babadan Among Beksa, yang bersama anak organisasinya Siswa Among Beksa, ikut membina kehidupan wayang wong di Yogyakarta. Sebelum tahun 2000 di yogyakarta tercatat beberapa organisasi tari yang menaruh minat pada wayang wong, yakni antara lain Krida Beksa Wirama, Bebadan Among Beksa, Mardawa Budaya, dan Pamulangan Budaya Ngayogyakarta (Bandem, dkk., 1996: 91-92). (2) Wayang Wong Gaya Surakarta Adapun wayang wong gaya Surakrta diciptakan oleh Sri Mangkunegara I dan mengalami perkembangan pesat pada jaman Sri Mangkunegara VII (19151944). Sri Mangkunegara VII memiliki perhatian besar pada kesenian Beliau menentukan sendiri para pemain wayang wong yang tak hanya terbatas dari kerabat istana, bentuk danwarna pakaian penari, mengawasilatihan, memimpin pertunjukan dan menyusun koreografinya. Tahun 1930 beliau mendirikan dan mengawsi sendiri sekolah tari agar dapat memilih penari yang baik. Konsep wayang wong Mangkunegaran juga mengambil ide dasar dari wayang kulit Purwa. Misalnya, lantai pendhopo yang memanjang sebagai arena pergelaran, menyiratkan kelir dalam wayang kulit. Posisi penari yang miring seperti hlnya wyang kulit di kelir. Di Yogyakarta, sejak diciptakannya wayang wong tahun 1758 sampai dengan tahun 1939 di istana, berfungsi sebagai ritual kenegaraan, baik untuk memperingati berdirinya keraton Yogyakarta, merayakan perkawinan agung putra-putri Sultan, dsb. Sedang wayang wong gaya Mangkunegaran Surakarta, lebih berkembang sebagai pertunjukan sekuler (Soedarsono, ……) Bila wayang wong Yogyakarta banyak mengambil sumber cerita dari Mahabharata, wayang wong Mangkunegaran banyak bersumber dari Ramayana. Dua lakon yang cukup terkenal pada waktu Mangkunegara VII adalah Anoman Duta (dari Ramayana dan Pregiwo-Pregiwati (dari Mahabharta). Pertunjukan wayang wong gaya Surakarta memang tidak semegah dan berlangsung lama seperti di Yogyakarta, namun juga tidak terjerumus dengan tambahan dekorasi realistik yang tampak tidak serasi. Bila peran putri di Yogyakarta dilakukan oleh penari pria, sebaliknya di Surakarta peran putri tetap diperankan oleh penari 168 putri. Bahkan selanjutnya, peran kesatria halus seperti Arjuna, Abimanyu juga dimainkan oleh penari putri. Dukungan Mangkunegara dan para penarinya menimbulkan inspirasi untuk tampil di luar istana. Prakarsa itu dilanjutkan Pakubuwono X dengan mendirikan taman hiburan rakyat Sri Wedari pada 1910. Taman yang semula kebun binatang, akhirnya dilengkapi dengan berbagai pertunjukan termasuk wayang wong. Dari sinilah wayang wong berkembang ke luar istana dengan berbagai dekorasi realistis, seperti pendhapa, balairung, hutan, jalan di pedesaan dengan sawah-sawah. Keberhasilan wayang wong Sri Wedari membuat para pemodal (terutama keturunan Cina) untuk mendirikan grup wayang wong. Mereka lalu keliling antar kota, dan akhirnya menetap di kota-kota lain. Hingga kini yang masih dapat diingat, yakni grup Senyo Wandowo (1929), Sri wanito (1935), Ngesti Pandowo (1962). Ngesti Pandowo (1957) dan Sri wanito menetap di Semarang, Sri Pandowo di Surabaya, Wayang Kosambi di Bandung, dan Bharata di Jakarta (1972). Setelah kemerdekaan, grup-grup tari di luar istana yang berperhatian pada wayang wong antara lain, Pusat Kesenian surakarta (1946), Himpunan Budaya Surakarta (1951), dan angkatan Muda Seni dan Karawitan Surakarta (1957). Pada 1962 di Surakarta diselenggarakan Festival Wayang Orang Amatir se Indsonesia. Kota Surakarta diwakili oleh tiga organisasi, yakni Himpunan Pecinta Seni Tari dan Karawitan (HPSTK), Dharma Budaya, dan Perkumpulan Masyarakat Surakarat (PMS). Dharma Budaya dan PSM terdiri dari masyarakat keturunan Cina. Selain itu, festival diikuti peserta dari berbagai kota, seperti dari Semarang, Bandung, Surabaya, Malang, Jakarta bahkan Tanjung Karang (Lampung). Pada 1966 di Jakarta juga diselenggarakan festival wayang wong. Namun pesertanya hanya bergaya Surakarta saja, yakni Sri Wandowo dari Surabaya, Ngesti Pandowo dan Sri Wanito dari Semarang, Sri Wedari dari Surakarta, dan Adi Luhung, Ngesti Pandowo, dan Panca Murti dari Jakarta. Jadi bila wayang wong gaya Yogyakarta hampir tidak mengenal grup komersial, di Surakarta 169 grup-grup komersial justru lebih banyak berkembang (Bandem, dkk., 1996: 9396). (b) Sumber Cerita Wayang Wong Seperti wayang purwa, sumber cerita wayang wong berasal dari Ramayana dan Mahabharata, yang kemudian berkembang dalam berbagai lakon, baik lakon baku, lakon carangan atau lakon sempalan. Naskah pertunjukan wayang wong berkembang dari penulisan yang sederhana dan praktis, yakni terdiri atas Serat Kandha saja, kemudian menjadi naskah yang lengkap dan dihiasi berbagai ornamen. Karena lengkapnya dan indahnya, salah satu naskah Serat Kandha dan Serat Pocapan wayang wong pernah mendapat komentar Pigeaud dalam Literature of Java sebagai edition de luxe. Serat Kandha dan Serat Pocapan yang paling tua tersimpan di Kraton Yogyakarta adalah berangka tahun 1845 berjudul Kagungan Dalem Serat Bragola Murti, manuskrip Kraton Yogyakarta No. 3/ 38. Para pakar budaya dari kraton Yogyakarta selalu menyatakan bahwa tradisi penulisan teks wayang wong yang berbentuk Serat Kandha dan Serat Pocapan dimulai oleh Sultan Hamengkubuwana V (1921-1939). Menurut Soedarsono hal itu tidak tepat. Tradisi penulisan seperti itu telah dimulai sejak Sultan Hamengkubuwana I (1755-1792). Hal itu terbukti dengan ditemukannya naskah berjudul Serat Kandha Ringgit Purwa yang tersimpan di India Office Library di London berkode Ms IOL Jav. 19. Manuskrip itu ditulis atas perintah Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegara Sudibyaprana Raja Putra Narendra Mataram (Putera mahkota Sultan Hamengkubuwana I. Manuskrip itu mulai ditulis pada 17 Nopember 1781 hingga 2 Januari 1782. Tiadanya Serat Kanda Ringgit Tiyang dari tahun 1845 karena Thomas Stanford Raffles (18111816) membawa manuskrip-manuskrep Jawa ke Inggris (Soedarsono…..) (c ) Pendukung Pertunjukan dalam Wayang Wong Berdasarkan tugasnya, anggota rombongan atau para pendukung pertunjukan wayang wong dapat dibedakan sebagai berikut. 170 1) Dalang Dalang dalam wayang wong, seperti halnya dalam wayang kulit, namun tidak menggerakkan wayang. Dalang adalah seorang juru cerita yang bertugas membantu atau mengatur laku dan jalannya pertunjukan, antara lain sebagai berikut. (a) memberikan narasi tentang apa yang sudah, tengah, dan akan terjadi (pocapan, kandha dan carita), mengisi suasana adegan dengan nyanyian berupa suluk, sendhon dan ada-ada (b) Memberikan tanda-tanda (sasmita), baik lewat kata-kata atau lewat bunyi keprak dan kecrek, kepada pemain gamelan, juga untuk menentukan gendhing apa yang akan dimainkan, dan kepada pemain di atas pentas tentang pergantian adegan, berakhirnya adegan, kedatangan tamu, dsb. Di Surakarta, tugas dalang sebagai pengatur laku atau adegan di atas pentas digantikan oleh petugas lain yang disebut meester. Di Yogyakarta, sejak jaman Sri Sultan Hamengkubuwana VI, tugas dalang sebagai juru cerita dan penyampai ungkapan-ungkapan verbal lain, digantikan oleh seorang pamaca (pamaos) kandha (pembaca cerita). Pamaca kandha tidak menghafalkan apa yang menjadi tugasnya, tetapi cukup membaca teks yang tertulis dalam Serat Kandha, yang juga memuat dialog para pemain secara lengkap. Tugas dalang sebagai pengeprak juga diganti oleh petugas lain (Bandem, dkk., 1996: 83). 2) Penari, Pemain atau Pelaku Wayang wong dimainkan oleh para penari pria dan wanita, dengan tugas yang hampir sama dengan klasifikasi penokohan dalam wayang purwa sebagai berikut. (a) Para kesatria dengan rajanya masing-masing (b) Para raksasa dengan dari kerajaan Sabrang (seberang) dengan rajanya yang bisa berwujud raksasa maupun manusia jahat (c) Para abdi, yakni abdi kesatria disebut Panakawan (Semar, Gareng, Petruk, Bagong), abdi tokoh-tokoh dari Sabrang (Togog dan Mbilung), 171 abdi tokoh puteri (Limbuk dan Cangik), dan abdi di pertapaan yang disebut Cantrik. Para abdi ini membawakan watak lucu atau gecul. (d) Pendeta dan Cantriknya (e) Para dewata (f) Para Binatang. Dalam Ramayana, banyak golongan kera yang dapat berbicara seperti manusia 3) Petugas Pengiring Petugas pengiring, yakni yang memainkan gamelan yang disebut pengrawit, para pengiring suara (vokalis) putri yang disebut pesindhen atau sindhen atau waranggana, dan para pengiring suara (vokalis) pria yang disebut penggerong. Penggerong sering juga merangkap sebagai pengrawit. 4) Petugas lain yang berhubungan dengan teknis panggung, yakni penarik layar, pengatur cahaya, petugas yang merawat pakaian, dsb. (Bandem, dkk., 1996: 83-84). (d) Struktur Dramatik Wayang Wong Struktur dramatik wayang wong pada dasarnya mengikuti struktur dramatik wayang kulit purwa selama semalam suntuk. Di kraton Yogyakarta, pada mulanya penyelenggaraan wayang wong lebih lama dari pada wayang kulit. Wayang wong dimulai pukul 06.00 pagi hingga pukul 23.00 malam. Bila wayang kulit, pathet nem-nya berlangsung jam 21.00 - 24.00, pada wayang wong berlangsung jam 06.00 - 12.00. Pada wayang kulit, pathet sanga-nya berlangsung jam 24.00 - 03.00, pada wayang wong berlangsung jam 12.00 - 18.00. Pada wayang kulit, pathet manyura-nya berlangsung jam 03.00 - 06.00, pada wayang wong berlangsung jam 18.00 - 23.00. Sebagai contoh, pada tahun 1926, dalam rangka merayakan perkawinan putra-putri Sultan, dilaksanakan pertunjukan wayang wong dengan lakon Mintaraga, yang merupakan kelanjutan dari lakon Bomantara atau Somba Sebit. Lakon Mintaraga dilaksanakan selama dua hari, dengan pembagian adegan sebagai berikut. 172 Bagian I dari jejer di Dwarawati sampai dengan terbunuhnya sekutusekutu Winatakwaca (Niwatakawaca). Bagian II dari adegan di Kahyangan Ngendrabawana sampai dengan terbunuhnya Niwatakawaca oleh Arjuna. Hari I: pathet nem: jejer Dwarawati sampai dengan jejer sabrangan di Kerajaan Ngimantaka. Pathet sanga: dimulai gara-gara dan jejer pandhita, perang kembang antara Abimanyu melawan empat raksasa, sampai dengan jejer di Ngamarta. Pathet manyura: perang antara para dewa melawan para sekutu raja Niwatakawaca dan jejer tancep kayon di Kahyangan Ngendrabawana. Hari II: pathet nem: jejer di Kahyangan Ngendrabawana sampai dengan jejer sabrangan di Kerajaan Ngimantaka dan perang antara para dewa dengan tentara Niwatakawaca. Pathet sanga: gara-gara dan jejer pandhita, perang kembang antara Mintaraga melawan para tentara Niwatakawaca dari Ngimantaka, sampai dengan jejer di Ngendra Sonya tempat Kresna bertemu dengan para Pandawa kecuali Arjuna. Pathet manyura: perang besar antara Mintaraga melawan Niwatakawaca, ditutup dengan jejer tancep kayon di Kahyangan, Batara Narada memerintahkan para dewa untuk menyiapkan perkawinan antara Mintaraga atau Arjuna dengan Dewi Supraba. Pada mulanya tema-tema yang ada yakni konflik antara dua bersaudara, kesuburan (perkawinan), dan keadilan. Menurut Soedarsono, tema-tema yang ada pada saat itu berhubungan dengan peristiwa-peristiwa penting yang berhubungan dengan istana Yogyakarta. Lakon Gandawardaya yang dipentaskan pertama kali oleh Sultan Hamengkubuwana I melambangkan konflik antara Sultan Hamengkubuwana I dengan Pakubuwana II dan III, yang baru selesai dengan campur tangan Belanda yang dilambangkan dengan Semar. Lakon perkawinan yang berhubungan dengan peristiwa perkawinan putera puteri Sultan, antara lain lakon Jaya Semadi, Bragolamurti, PregiwaPregiwati, Sri Suwela, Parta Krama, Srikandhi Maguru Manah, Sumbadra Larung, dan Mintaraga. Tema tentang keadilan antara lain terdapat pada lakon Bomantara atau Somba Sebit, yang menceritakan tentang kematian Somba dan kematian Boma atau Narakasura. 173 Lakon Petruk Dados Ratu dipentaskan oleh Sultan Hamengkubuwana V, merupakan sindiran untuk Komisaris Jenderal Leonard Pierre Joseph Burgraaf Du Bus Da Gisignies yang bukan darah keturunan Jawa tapi ingin memerintah sebagai raja. Saat itu Petruk dipentaskan berpakaian jenderal (Soedarsono,….) Pada pementasan di luar istana Yogyakarta, juga seperti struktur dramatik wayang kulit purwa yang dibagi menjadi tujuh adegan. Hanya saja, adegan-adegan dalam wayang wong lebih dipadatkan. Bila wayang kulit berlangsung semalam suntuk sekitar sembilan jam, dalam wayang wong hanya berkisar tiga jam. Rincian ketujuh adegan tersebut sebagai berikut. 1. Adegan pertama (jejer Kawitan) yang menggambarkan persidangan di kerajaan besar (seperti Astina atau Amarta), yang akan menjadi pusat perkembangan lakon. Kalau ada perangnya disebut Perang Rempak. 2. Jejer Sabrangan yang selalu diikuti dengan peramng yang disebut Perang Simpangan atau Perang kadung 3. Jejer Bondhet, yang diikuti dengan perang gagal 4. Jejer Pandhita (Pendeta) yang didahului atau diikuti adegan gara-gara (munculnya para Panakawan). Adegan ini diikuti oleh perang yang disebut Perang Kembang 5. Jejer Uluk-uluk, yang diikuti oleh perang cilik (persang kecil) karena hanya terjadi antara prajurit-prajurit kecil 6. Jejer Sumirat, yang diikuti perang tanggung, karena yang maju baru para prajurit menengah. 7. Jejer Rina-rina, diikuti perang yang disebut Perang Brubuh, yakni perang yang terjadi banyak korban hingga berakhir dengan terbunuhnya raja raksasa jahat (Bandem, dkk., 1996: 88). 3) Langendriyan Langendriyan sering juga disebut langendriya. Kata langen berasal dari kata langö bahasa Jawa Kuna yang berarti ‘indah’. Dalam bahasa Jawa Baru kata langen berarti ‘hiburan’. Kata turunan lainnya yang mirip adalah klangenan yang juga berarti ‘hiburan’ atau ‘kesenangan’. Kata driya berarti ‘hati’. Jadi maksud 174 kata langendriyan mungkin ‘hiburan hati’. Langendriyan adalah drama tari Jawa yang menggabungkan unsur tari, karawitan dan drama. Sebagian pemerhati menyatakan bahwa langendriyan adalah karya R.M. Tandakusuma (jaman Mangkunegara V). Sedang dalam Ensiklopedi Indonesia jilid IV (1983: 1960), tercatat bahwa langendriyan adalah jenis drama tari Jawa yang menitikberatkan pada unsur tari dan seni suara. Seluruh dialog dalam drama tari itu berbentuk tembang macapat sehingga boleh dikatakan semacam opera berbahasa Jawa. Ceritanya khusus mengenai siklus Damarwulan- Minakjingga dari jaman Majapahit. Bentuk ini dirintis oleh R.M. suparto (Mankunegara IV, 1853-1881) dan dikembangkan dari istana Mangkunegaran Solo oleh R.M.H. Tandakusuma, yang juga menulis liberto untuk beberapa lakon langendriyan. Bambang Sriyono (Kompas Minggu, 1983) membantah keterangan di atas. Menurut dia, pencipta langendriyan adalah K.P.H. Purwodiningrat, kemudian dikembangkan oleh adik iparnya. Atas jasa G.P.H. Mangkubumi (putra Hamengkubuwana VI, 1855-1877), langendriyan menjadi besar. Setelah tujuh tahun langendriyan lahir, Mangkunegara berkenan meminjam catatan tatalaku langendriyan. Selanjutnya R.M.H. Tandakusuma (menantu Mangkunegara IV) diperintahkan untuk mengubah dengan gerak dan gaya Surakarta. Langendriyan tampil di Mangkunegaran pada saat pengangkatan putra mahkota menjadi Sri mangkunegara V, pada 15 Desember 1881) Menurut Ben Suharto dan kawan-kawan, langendriyan lahir antara tahun 1855-1913, buah karya tokoh seniman bangsawan Yogyakarta, Raden Tumenggung Purwadiningrat, yang selanjutnya dikembangkan oleh iparnya, yakni KGPA Mangkubumi, putera Hamengkubuwana VI (Suharto, 1999: 16). Berbeda dengan wayang wong yang lahir diistana, langendriyan lahir di luar tembok kraton. Di Surakarta langendriyan kemudian diangkat menjadi kesenian istana Mangkunegaran. Sedang di Yogyakarta, langendriyan yang lahir dengan dukungan para bangsawan istana tidak pernah resmi menjadi tontonan milik istana (Bandem, dkk., 1996: 106) Langendriyan, baik di Surakarta dan di Yogyakarta, mengambil sumber cerita dari Serat Damarwulan, yang mengisahkan Ratu Kencanawungu dari 175 Majapahit dalam usahanya membasmi pemberontakan Adipati Minakjinggo di Blambangan. Minakjinggo akhirnya dapat dibunuh oleh Damarwulan dan Damarwulan menikah dengan Kencanawungu. 4) Langen Mandra Wanara (Langen Wanara) Langen mandra wanara terdiri atas tiga kata bahasa Jawa, yakni lanngen, mandra dan wanara. Kata langen berarti ‘bersenag-senang’ atau ‘hiburan’, mandra berarti ‘banyak’ dan wanara berarti ‘kera’ (Suradjinah, via Suharto, 1999: 17). Menurut Padmopuspito (via Suharto, 1999: 17) mandra dalam bahasa Kawi (Jawa Kuna) juga bersinonim dengan kata langen yang berarti ‘indah permai’. Dengan demikian langen mandra wanara dapat berarti pertunjukan banyak peran kera yang dimaksudkan untuk menyenangkan hati. Drama tari opera ini mempunyai kekhasan yakni, melakukan gerakan tari dengan posisi jengkeng atau menggunakan lutut sebagai penyangga dalam gerak-gerik tarinya. Langen mandra wanara diciptakan oleh KPAA Danureja VII, pada 1890. Dalam beberapa sumber disebutkan bahwa KPAA Danureja VII kemudian bergelar KPH Cakraningrat. Dalam sumber yang lain lagi disebutkan bahwa pendirinya adalah KPH Yudanegara III, atau ada yang menyebutkan bahwa pendirinya adalah KPH Cakradiningrat. Hal ini dijelaskan oleh Ben Soeharto bahwa KPH Cakraningrat adalah gelar Danureja VI setelah pensiun sebagai patih, bukan Danureja VII. Danureja VII menjabat patih Keraton Yogyakarta hingga akhir hayatnya, dan tetap menggunakan nama KPAA Danureja VII. Sebelum menjabat sebagai patih, Danureja VII memang bergelar KPH Yudanegara III, dan setelah menikah dengan BRAy Cakradiningrat, putri Sultan Hamengkubuwana VII, beliau juga bergelar KPH Cakradiningrat. Jadi jelaslah 176 bahwa Danureja VII sama dengan KPH Yudanegara III, sama dengan KPH Cakradiningrat, tapi bukan KPH Cakraningrat (Suharto, dkk., 1999: 12-14) Ketika masih muda KPH Yudanegara III memang pecinta seni, terutama seni tari. Karena di luar kraton tidak boleh meniru kesenian kraton, maka beliau menampilkan kesenian rakyat yakni Srandhul. Ayahandanya, yakni Yudanegara II, tidak senang, dan menyarankan agar mengubah lakon Ramayana dalam bentuk kesenian yang bercorak garapan istana. Yudanegara III tampaknya tidak tertarik pemakaian topeng dalam tari, sehingga meniru bentuk yang telah lebih dulu ada yakni langendriya. Oleh karena itu akhirnya diberi nama Langen Mandra Wanara. Bila catatan kelahiran langen mandra wanara pada tahun 1890 atau tahun 1895 benar, maka kegiatan tari di Mangkunegaran memang terhenti pada pemerintahan Mangkunegara VI (1896-1916). Bisa diduga bahwa langen mandra wanara berdiri dengan penanganan seniman Yogyakarta dulu, kemudian setelah tahun 1896, RMH Tondokusumo datang ke Yogyakarta untuk mengembangkan langen mandra wanara di Surakarta. RMH Tondokusumo memang lebih tua dari KRT Joyodipuro, namun keduanya bersahabat dan sama-sama memiliki ilmu Hasta Sawanda, yakni delapan prinsip dasar tentang tari Jawa (Suharto, 1999: 19). Lahirnya langen mandra wanara merupakan jawaban untuk menciptakan kreasi yang bermutu sekaligus tidak menyamai kesenian milik kraton yang memang dilarang dipentaskan di masyarakat luar kraton. Langen mandra wanara terbukti berkembang merakyat ke pelosok pedesaan. Setelah Perang Dunia I, organisasi angkatan muda Jong Java mengirimkan R. Wiwoho dan RM. Noto sutarso, untuk menemui tokoh-tokoh tari keraton Yogyakarta agar mau mengadakan pelajaran atau sekolah tari dan karawitan. Maka pada 17 Agustus 1918 berdirilah perkumpulan Krida Beksa Wirama, dengan ijin dan restu Sri Sultan Hamengkubuwana VII. Pangeran Soerjodiningrat dan Pangeran Tedjakusumo, merupakan dua tokoh yang besar andilnya dalam Krida Beksa Wirama (Suharto, 1999: 38). Tentu saja perkembangan langen mandra wanara juga ditunjang oleh perkumpulan tersebut. 177 Pada tahun 1961, atas anjuran Menteri P dan K, untuk menghidupkan kembali kesenian rakyat, dibentuk Badan Pendorong Kesenian Rakyat oleh Kepala Inspeksi Daerah Kebudayaan Perwakilan departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Kusumobroto. Dalam rangka penggalian kembali itu, pada 12 Nopember 1961, dalam rangka ulang tahun Krida Beksa Wirama ke-43, dipentaskanlah langen mandrawanara. Kemudian juga ditunjuk C. Hardjosoebroto untuk menangani pembaharuan langen mandrawanara. Perubahan atau pembaharuan yang terjadi menghasilkan langen mandra wanara gaya baru, antara lain dengan perubahanperubahan sebagai berikut. a. Perubahan tari jongkok ke tari berdiri b. Kandha diringkas dan digarap dalam bentuk tembang dan gerong. c. Percakapan disusun baru dan ringkas d. Gendhing diberi gerongan baru. e. Senggakan oleh para waranggana dihapuskan. f. Gendhing ditata silih berganti antar laras pelog dan slendro. Pada 7 Juli 1962 di Bangsal Kepatihan telah dipentaskan dengan berbagai perubahan. Kehadiran Menteri P dan K, Wakil Kepala Daerah Sri Paku alam VIII, serta tokoh seniman budayawan Yogyakarta ketika itu telah menjadikan semangat baru dalam kehidupan langen mandra wanara. Mulai tahun 1974, dua kali tiap tahun, di bawah Kepala Inspeksi Kebudayaan Dinas P dan K DIY, yakni R. Pangarsobroto, menyelenggarakan pementasan seni tari dari DIY yang biasanya diselenggarakan di Bangsal Kepatihan. Event ini menjadi ajang pertemuan seniman dan budayawan DIY. Dalam event itu langen mandrawanara berkesempatan untuk pentas, antara laian pada tahun 1976 grup langen mandra wanara dari Notoyudan mementaskan lakon Subali Mukswa. ISI (Institut Seni Indonesia) yang dulu bernama ASTI Yogyakarta, sejak 1977, memasukkan kurikulum akademis, yakni pada Kelas Tari Jawa Yogyakarta III, dengan memberikan kesempatan pada mahasiswanya untuk salah satunya belajar langen mandrawanara. 178 Perkembangan yang juga penting untuk dicatat ialah penyebarluasan langen mandrawanara dalam media radio dan media kaset rekaman. RRI Nusantara II Yogyakarta, tercatat menjadwalkan siaran langen mandra wanara setiap sebulan atau dua bulan sekali, di bawah asuhan Ki Banjaransari, yang sering menempatkan diri sebagai pamaca (pamaos) kandha, yakni pembaca narasi cerita dalam teks. Dalam media rekaman, hingga saat ini, setidak-tidaknya tercatat beberapa rekaman langen mandrawanara, antara lain sebagai berikut. 1. Ki Cokrowasito, Mondrowanaran Kidang Kencana, produksi Irama Mas. 2. Ki Cokrowarsito, Mondrowanaran Subali Gugur, produksi Irama mas. 3. Ki Cokrowarsito, Mondrowanaran Sinto Taman, produksi Irama Mas. 4. Bagong Kussudiarjo, Langen Mandrawanara, Senggana Gandrung, “Sapta mandala”/ Kodam VII Diponegoro, produksi Fajar. 5. Ki Nartosabdo, Langen Mandrawanara, Mangkat Ngayahi Duto, Vol. I, Karawitan Condongraos, Produksi Singo Barong (Suharto, 1999: 4247). Dalam sejarah perkembangannya, di Yogyakarta, setidak-tidaknya tercatat beberapa kampung yang pernah memiliki grup langen mandra wanara, yakni sebagai berikut. 1. Tahun 1921 berdiri Langen Mandrawanara Mataram, dengan tokohnya R.Ng. Manitisudira, yang kemudian diambil alih oleh KRT Yudokusumo. Grup ini pernah mengadakan pentas di Pura Mangkunegaran dalam rangka penobatan Mangkunegara VIII dengan lakon Sugriwa-Subali. 2. Grup langen mandrawanara di kampung Notoyudan didirikan tahun 1925 oleh KRT. Condronegoro. Setelah beliau pindah ke Condronegaran, maka diteruskan dengan bimbingan Raden Lurah gandrung ( R.Ng. Hasthokuswolo). 3. Berdiri di kampung Kumendaman tahun 1928. Tokoh yang meneruskan adalah KRT. Mandiyokusumo. 4. Di kampung Sosrowijayan berdiri sekitar tahun 1938-1939 di bawah pimpinan Bandara Raden Mas Cornel, putera dari Kanjeng Gusti Putra. 179 5. Krt. Condronegoro mendirikan juga langen mandra wanara di kampung Condronegaran. 6. Pada 1942 berdiri di kampung Tegalgendu, Kotagede, dipimpin oleh KRT. Purwonegoro. Grup ini pernah mementaskan lakon Sinto Boyong hingga Perkawinan jembawan, dengan merubah posisi jongkok menjadi berdiri. 7. Perkumpulan Mardi Guna. (Suharto, 1999: 39-40) Adapun perkumpulan langen mandrawanara di luar kota Yogyakarta antara lain terdapat di Kabupaten Bantul dan Sleman. Di Kabupaten Bantul, yakni sebagai berikut. 1. Di Desa Desa Sembung, Kelurahan Bangunjiwa, Kecamatan Kasihan, pada tahun 1945 masih ada. Ketika itu murid Dwijowiyoto ikut pentas sebagai kera atau kethek. 2. Di Desa Padokan, Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, dipimpin oleh Gurisa. 3. Di Kelurahan Jambitan, Kecamatan Banguntapan 4. Di Desa Nanggulan, Keurahan Gadingsari, Kecamatan Sanden 5. Di Desa Wonolopo, Kelurahan Canden, Kecanatan Jetis. Di Kabupaten Sleman nama Langen Mandrawanara juga sering disebut Purba Wanara. Di kabupaten ini antara lain pernah ada perkumpulan di beberapa tempat, sebagai berikut. 1. Di Desa Morangan, Kelurahan Triharjo, Kecamatan Sleman, muncul kira-kira tahun 1936. 2. Di Desa Kumbangarum, Kelurahan Danakerta, Kecamatan Turi 3. Di Desa Pulowatu, Kecamatan Turi, dengan pentas terakhir sekitar tahun 1964 (Suharto, 1999: 41-42). Sumber Cerita Langen Mandra Wanara Langen mandra wanara, sesuai dengan namanya secara dominan berisi tarian kera. Cerita tentang kera-kera tersebut diambil dari sumber cerita Ramayana dan cerita Lokapala. Lakon-lakon yang sering dipentaskan antara lain: Sinta Ilang, Subali Lena, Anggada Duta, Senggana Duta, Wibisana Tundhung, 180 Wibisana Balik, Rama tambak, Kumbakarna Gugur, Brubuh Alengka, Sumantri Ngenger, Bedhahing Lokapala, dsb. 5) Kethoprak Menurut Padmosoekotjo (tt, Jilid II: 65) kethoprak muncul di Sala pada tahun 1920, tetapi berkembangnya di Yogyakarta. Kethoprak sangat populer dengan mempertontonkan cerita bermacam-macam dan dengan dialog tembang dan gancaran (prosa). Kethoprak merupakan kesenian rakyat tradisional yang sangat populer di tengah-tengah masyarakat Jawa, terutama di wilayah Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur. Nama kethoprak berasal dari bunyi-bunyian yang berbunyi “prakprak”, seperti halnya alat pertanian masa dulu yang disebut tiprak. Pertunjukan kethoprak bermula dari pertunjukan drama yang sangat sederhana, dengan dialog bahasa sehari-hari. Pada mulanya pertunjukan itu menggunakan iringan dengan memukul perangkat penumbuk padi yang disebut lesung. Kemudian berkembang dengan iringan gamelan dan dengan pengayaan cerita dari cerita-cerita rakyat, cerita-cerita dari babad, cerita-cerita dari luar negeri dan kemudian berbagai cerita dapat dipentaskan dalam kethoprak. Pada mulanya dan pada sebagian besar pementasan kethoprak saat ini, masih menggunakan pola lama dalam menghidangkan lakon-lakonnya, karena pada dasarnya lakon kethoprak itu sendiri sudah mendarah-daging meniru lakon wayang, yang dimulai dari jejeran hingga selesai tancep kayon (Soemardjono, 1987: 6). Kethoprak memiliki kekhasan dibanding dengan beberapa jenis drama tradisional lainnya, yakni sifat kelenturannya. Kelenturan dan keluwesan yang menjadi sifat kethoprak dapat dilihat dari munculnya beragam jenis ketoprak. Kemunculan kethoprak lesung yang disusul oleh kethoprak ongkek (barangan), kethoprak pendhapan (tanggapan), kerthoprak panggung (tobong), radio, hingga TV, menunjukkan bahwa kelenturan dan keluwesan tersebut menjadi senjata ampuh bagi kethoprak untuk terus bertahan melawan tantangan jaman (Nusantara 1997: 52). 181 Kelenturan kethoprak juga tampak pada pemilihan sumber lakonlakonnya. Kethoprak dapat saja mementaskan berbagai cerita yang bersumber pada cerita wayang purwa, cerita babad, cerita rakyat, cerita dari luar negeri, bahkan cerita yang bersumber dari novel-novel paling mutakhir pun. Jadi mulai dari cerita yang bersifat istanacentris dari abad sebelum Masehi hingga cerita tentang masyarakat kampus UNY tahun 2006 ini pun dapat dipentaskan dalam kethoprak. Oleh karena kelenturan bidang garapan kethoprak tersebut, struktur dramatiknya juga luwes, artinya dapat bersifat tradisional dengan pola wayang purwa atau jauh menyimpanginya. Hal ini menyangkut berbagai unsur struktur yang ada dalam kethoprak. 6) Wayang Beber Menurut Padmosoekotjo (tt, jilid II: 63), disebut wayang beber karena pementasannya dengan dibeber atau dijereng (bahasa Jawa) yang berarti diceritakan sambil dibentangkan gambarnya yang ada pada kain. Menurut Hazeu lebih masuk akal bila pertunjukan bayangan dan topeng telah muncul lebih dulu, baru kemudian sampai pada taraf perkembangan yang lebih tinggi, yakni dengan melukiskan apa yang dianggap sebagai nenek moyangnya, pada kain serta mewarnainya yang kemudian disebut wayang beber. Menurut KPA Kusumadilaga dalam buku karyanya Sastramiruda, menyebutkan bahwa wayang beber dibuat oleh Prabu Bratana dari Majapahit pada tahun 1361 M atau 1283 Saka dengan sengkalan guna bangsa nembah ing dewa. Ketika itu telah dilukiskan lakon Murwakala dan dipentaskan dengan gamelan laras Slendro. Wayang beber sebagai seni pertunjukan pertama kali didokumentasikan oleh dua orang cina, yakni Ma Huan dan Fei Xin yang mengunjungi Jawa pada 182 tahun 1416. Keduanya menyaksikan orang-orang berjongkok di depan pencerita (dalang) dan mendengarkannya. Kepada orang-orang itu ditunjukkannya gambar (oleh dalang). Perkembangan gulungan bergambar mewakili perkembangan bentuk “gambar diam” yang asli (dan menunjukkan perkembangan cerita). Empat abad kemudian Raffles dalam buku History of Java nya menggambarkan wayang beber sebagai “penemuan modern secara komparatif dan tak terlalu dihargai”. Akhir-akhir ini untuk masa yang lama wayang beber dikira telah mati. Namun pada tahun 1963 masih ditenukan dua set gulungan wayang beber itu di desa Karang Talun di perbukitan Gedompol Gunung Kidul. Pada gulungan yang lebih tua ditanggali dengan kronogram (candra sengkala) yang dapat ditafsirkan sebagai tahun 1690. Tiap gulungan berukuran sekitar 200 X 70 cm, meliputi empat adegan horizontal yang dilukis dengan cat. Kisah atau lakon yang digambarkan pada perangkat gulungan yang pertama adalah Panji Jaka Kembang Kuning, berasal dari jaman Majapahit, akhir abad ke-13 - awal abad ke-16. Panji dalam cerita ini menjalani berbagai cobaan dalam pengembaraan dan melalui pertempuran-pertempuran yang mempertaruhkan nyawa, namun akhirnya dapat memperoleh kekasihnya yakni Dewi Sekar Taji. Dewi Sekar Taji adalah putri raja Brawijaya dari kerajaan Kediri. Dewi Sekar Taji menghilang pergi dari istana untuk menghindari pernikahan paksa dengan Raja Klana Jaka yang dibenci karena tabiatnya yang buruk. Ayahnya mengumumkan bahwa barang siapa dapat membawa kembali Sekar Taji, maka ia berhak menjadi suaminya. Panji Jaka Kembang Kuning berhasil menemukannya dan membawanya kembali ke istana. Raja Klana Jaka dengan kelicikannya masuk ke taman keputren tetapi tertangkap oleh putra mahkota raja sehingga diusir dan terjadi pertempuran. Akhirnya Raja Klana Jaka terbunuh oleh pusaka Pasopati. Akhirnya Prabu Brawijaya mengumumkan bahwa Panji sebagai pemenang sayembara dan berhak menyunting Dewi Sekar Taji. Gulungan kedua menceritakan Remeng Mangun Jaya (nama Panji yang lain). Ceritanya hampir sama dengan gulungan pertama, yakni tentang keberhasilan Panji mendapatkan cintanya, namun dilalui dengan berbagai cobaan 183 hidup yang berbahaya dalam suatu pengembaraan (Indonesian Heritage: Bahasa dan Sastra, Jilid 10, Haryati Soebadyo, 50). Cara pertunjukan wayang beber yakni, dalang bercerita tentang kisah Panji. Sementara dalang bercerita, ia atau pembantunya membuka gulungan bergambar. Kisah atau lakon ditunjukkan pada bagian tertentu yang digambarkan pada kain atau kertas bergambar tersebut. Dari segi ceritanya, di Jawa tercatat ada tiga jenis wayang beber, yakni wayang beber purwa bersumber dari Ramayana dan Mahabharata, wayang beber gedhog yang menceritakan tentang cerita Panji dan wayang beber klithik yang menceritakan tentang Damarwulan. 7) Wayang Golek Dari segi bonekanya, wayng golek merupakan wayang tri matra yang terbuat dari kayu dengan segala atributnya, antara lain pakaian dari kain, gagang penggerak (tuding) dari bambu atau penyu dan pegangan yang disebut sogo yakni kayu atau bambu atau penyu yang menembus badan dan menyangga kepala. Wayang golek ditemukan di Jawa Tengah, Jawa Timur dan DI. Yogyakarta. Di DI. Yogyakarta wayang golek juga dinamai wayang thengul. Boneka wayang ini merupakan tri matra. Kata golek secara harfiah berarti ‘boneka’ atau ‘patung kecil’, tetapi juga berarti ‘mencari’. Pada wayang kulit purwa, pada saat akhir pertunjukan selalu diakhiri dengan pementasan tarian wayang golek yang sering dimaknai dengan kata golekana yang maknanya ‘carilah’, yakni carilah makna dari pertunjukan wayang kulit yang bersangkutan. Menurut Serat Centhini (awal abad ke-19) dan Serat Sastramiruda (awal abad ke-20), wayang golek Jawa diperkenalkan pada tahun Jawa 1506 (1584 M), sedang wayang golek purwa Sunda baru mulai dikenal di Priangan awal abad ke19 (Edi Sedyawati, 2002, jilid 8: 58). 184 Wayang golek dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis berdasarkan cerita yang dipentaskan, yakni sebagai berikut. 1) Wayang golek purwa yang mengambil cerita dari Mahabharata dan Ramayana. 2) Wayang golek menak yang mengambil cerita dari pustaka Serat Menak yang mendapat pengaruh dari perkembangan Islam, dengan tokoh Wong Agung Menak atau Jayengrana. 3) Wayang golek babad yang menceritakan babad (sejarah tradisional), seperti babad Majapahit, babad Pajajaran, dsb. Sekarang jarang sekali ditemukan. 4) Wayang Potehi yang mengambail cerita dari Cina Di Jawa wayang golek purwa sangat jarang ditemukan, dan kebanyakan wayang golek yang dipentaskan adalah wayang golek menak. Namun bila penanggap menghendaki dalang wayang golek untuk mementaskan cerita wayang purwa, biasanya dalang wayang golek menak pun bersedia. Ciri khusus pada wayang golek adalah bagian kepala dan tangan yang dapat digerakkan seperti gerak manusia. Kepala dapat dilepaskan pada saat dipenggal dalam pertunjukan sehingga lebih mendekati realita dibanding dengan wayang kulit. 8) Wayang Madya Wayang madya dipergelarkan seperti wayang purwa tetapi mengambil cerita setelah cerita Prabu Parikesit, yakni mulai Prabu Gendrayana di negara Astina hingga cerita Lembusubrata di negara Majapura (Padmosoekotjo, tt, jilid II: 63) Wayang Gedhog 185 Wayang gedhog atau sering disebut wayang wasana menceritakan cerita setelah Prabu Lembusubrata hingga cerita Panji Kudalaleyan di Pajajaran. Cerita paling populer adalah cerita Panji Putra dari Jenggala (Padmosoekotjo, tt, jilid II: 63). . Wayang Klithik Wayang klithik menurut Padmosoekotjo, tt, jilid II: 63) menceritakan cerita jaman Pajajaran dan Majapahit pada akhir pemerintahan Prabu Brawijaya. Cerita yang paling populer adalah cerita Damarwulan-Minakjingga. Wayang klithik yang juga disebut wayang krucil, dari segi bonekanya merupakan wayang dwi matra yang terbuat dari kayu yang dibentuk dan dicat. Seperti boneka wayang kulit, pada umumnya wayang krucil ini hanya dapat digerakkan pada bagian tangannya saja. Bila wayang kulit ditancapkan pada gedebog batang pisang, wayang krucil ditancapkan pada kayu yang berlubanglubang. Dalam Serat sastramiruda disebutkan bahwa wayang krucil pertama kali dibuat pada tahun 1571 Saka (1648 M) oleh Ratu Pekik di Surabaya. Pada umumnya cerita dalam wayang krucil bersumber dari Serat Damarwulan yang mengisahkan sebagian cerita dari babad Majapahit. Namun demikian di daerah tertentu ada juga yang mengambil cerita dengan bersumber dari Mahabharata (bdk. Edi Sedyawati, 2002, jilid 8: 59). 11) Wayang Suluh Munculnya setelah kemerdekaan yakni tahun 1946, menceritakan sejarah perjuangan Indonesia dan bertujuan untuk memberikan semangat pada rakyat Indonesia (Padmosoekotjo, tt, jilid II: 63). 186 12) Wayang Topeng Wayang topeng menceritakan seperti cerita-cerita dalam wayang gedhog, tetapi para penari menggunakan topeng (Padmosoekotjo, tt, jilid II: 65). Drama tari topeng (wayang topeng) , meskipun jumlahnya sudah sangat menyusut, namun masih ada sejumlah desa di Jawa yang melestarikan. Pada umumnya masyarakat pedesaan masih menggunakan istilah wayang topeng. Cerita yang dipentaskan juga masih berkisar pada cerita Panji. Memang ada pula yang menyebutnya enggreng. Selain cerita Panji enggreng juga mementaskan cerita Menak (Soekarno, 1979/ 1980, via Soedarsono, 1986:86) Seyogyanya tidak dilupakan usaha perkumpulan Krida Beksa Wirama untuk mengangkat pertunjukan wayang topeng sebagai kesenian rakyat pedesaan, yang kemudian digarap dengan gaya keistanaan. Langkah tersebut merupakan langkah mendampingkan kesenian rakyat pedesaan dengan seni tradisi istana (Suharto, 1999: 39). 13) Srandhul yang berasal dari kehidupan pedesaan ini sangat berbeda dengan kesenian kraton. Cerita yang digunakan mengambil dari Serat Menak, dengan instrumen bendhe, terbang, kendhang dan angklung. Lakon yang dibawakan bermacam-macam sesuai dengan permintaan yang menangggap. Beberapa lakon yang cukup terkenal antara lain, Rebutan pedhang kangkam, Ndhulang Mas, dan Jatikerna. Kadang diadakan selingan yang disebut gara-gara. Adegan ini tampaknya dipakai untuk memberi penerangan atau nasihat kepada masyarakat pedesaan agar dalam kehidupan sehari-hari tidak terperosok dalam kesulitan hidup (Suharto, 1999: 15) 187 14) Pethilan Pethilan, seperti halnya wayang wong, yakni dengan tarian, dengan dialog baik berupa tembang maupun prosa, tetapi juga seperti jenis tarian Wireng, yakni menekankan tentang keprajuritan (Padmosoekotjo, tt, jilid II: 64). 15) Pranasmara Pranasmara seperti halnya langendriya, tetapi ceritanya tidak hanya cerita peperangan di Majapahit, tetapi juga lakon wayang macam-macam (Padmosoekotjo, tt, jilid II: 65). 16) Drama Jawa Modern Sejak adanya pengaruh drama Barat dan cara pemanggungannya, pada permulaan abad 20 timbul bentuk drama baru di Indonesia, yaitu komedi stambul, tonil, opera, wayang wong, kethoprak, ludruk, dsb. Pementasan dramadrama ini belum menggunakan naskah (Sumardjo, 1992: 255). Teks drama ditulis dengan mengacu pada kemungkinan pementasannya. Pementasan drama, di samping harus mempertimbangkan berbagai inovasi pembaharuan, juga harus selalu mengacu pada berbagai aturan main yang telah bersifat konvensional dalam pementasan-pementasan sebelumnya. Hal ini menjadikan teks drama sangat terikat pada berbagai konvensi yang ada, baik konvensi penulisan maupun konvensi yang ada dalam pementasan. Di samping konvensi yang bersifat umum sebagai seni pertunjukan, setiap jenis drama memiliki kekhasannya masing-masing dalam hubungannya dengan konvensi yang melekatinya 188 Dalam bentuk drama tradisional, konvensi yang ada dalam pementasan akan semakin dipatuhi pada saat menulis maupun mementaskan drama. Hal ini dikarenakan penulis dan pemain drama tradisional mengacu pada kemungkinan keberterimaan masyarakat pada apa yang dihasilkannya. Inovasi dalam drama tradisional, pada umumnya hanya dapat diterima bila inovasi tersebut berada pada unsur-unsur atau bagian-bagian tertentu yang memang tersedia untuk dipakai sebagai unjuk kebolehan dengan berbagai inovasi. Dalam drama modern, konvensi yang ada relatif lebih sedikit dibanding dengan jenis-jenis drama tradisional. Oleh karena itu di sana-sini sangat terbuka untuk disisipkan inovasi. Bahkan berbagai konvensi yang ada sangat rentan untuk diabaikan atau bahkan diberontaki. Namun demikian bukan berarti bahwa dalam drama modern tidak ada konvensi yang berlaku, karena setiap jenis drama akan mengacu pada tujuan dan fungsinya yang berhubungan dengan masyarakat. Dengan demikian keberterimaan masyarakat akan selalu menjadi titik tolak yang diperhitungkan. Hal itulah yang menjadi tempat berperannya konvensi drama. Rendra (1983: 33) pernah berpendapat bahwa seni drama modern di Indonesia timbul dari golongan elite yang tak puas dengan komposisi drama rakyat dan seni drama tradisional. Dialog dalam drama tradisional hanya diimprovisasikan dan hanya dijadikan sampiran dalam cerita. Oleh karena itu naskah sandiwara mulai sangat dibutuhkan karena dialog yang dalam dan otentik dianggap sebagai mutu yang sangat dipentingkan. Menurut Moch Nursyahid P. (Makalah saresehan Bahasa dan Drama Jawa di PKJT Solo 23-26 Januari 1983) Sandiwara modern Jawa lahir melalui lomba penulisan naskah drama berbahasa Jawa dan pakeliran, yang diadakan oleh PKJT tahun 1980. Namun menurut catatan Suripan Sadi Hutomo, sandiwara modern Jawa lahir setelah RRI Nusantara II Yogyakarta menyiarkan sandiwara radio berbahasa Jawa, jauh sebelum tahun 1980-an. Acara ini kemudian ditiru oleh beberapa radio amatir. Jadi sandiwara modern Jawa telah lahir sebelum 1980-an. Sayembara dari Pengembangan Kesenian Jawa Tengah (PKJT) pada tahun 1979 menghasilkan juara dengan judul-judul sebagai berikut. Pangurbanan karya Aryono KD, Kali Ciliwung karya Moch Nursyahit P, Secuwil Ati lan 189 Wengi karya Suliyanto, Sadumuk Bathuk karya Poerwadhie Atmodhihardjo, Omah Warisan karya Suryadi WS, Males Budi karya Mang Oji, Antarane Ombak-ombak Gumulung karya Anjrah Lelonobrata, dan Kembang Warung karya L. Siti Aminah. Tiga buah judul yakni, Pangurbanan, Kali Ciliwung dan Secuwil Ati lan Wengi telah diterbitkan oleh PKJT tahun 1980. Sedang dalam sayembara PKJT tahun 1980 melahirkan drama Jawa berjudul sebagai berikut. Gandrung Kecepit karya Sarwoko Tesar, Tugas karya Soetiyatmi, Tumiyuping Angin Wengi karya Aryono KD, dan Taman karya Moch Nursyahit P. Tugas, karya Soetiyatmi dijadikan sebagai naskah Festifal Teater Bahasa Jawa di Semarang tahun 1982 (Hutomo, 1983: 64). Hingga saat ini sandiwara Jawa yang direkam dalam kaset audio antara lain : (1) Basiyo Gandrung , oleh Basiyo, dibawakan oleh Dagelan Mataram, direkan oleh Borobudur Recording, 1997, (2) Reca Mas, oleh Sumardjono, dibawakan oleh Grup Sandiwara Radio RRI Nusantara II Yogyakarta, 1979, (3) Jambret Bermata Mlolo, oleh Heru S., dibawakan oleh Komedi Jenaka KR, 1981, (4) Romantika di Rumah Duda, oleh Handung KS, dibawakan oleh Komedi Jenaka KR, 1981), (5) Dokter Gadungan oleh Dipo Winoto, dibawakan oleh Grup Teater Angkatan Muda, 1981. Naskah-naskah drama TV karya Heru Kesawa Murti antara lain: Mbleber Kejewer (Nopember 1990), Pinter Merga Maca (Desember 1990), Panen Kacang (Januari 1991), Guyub (Februari 1991), Sepele Dadi Gawe (Maret 1991), Kewirangan (April 1991), Keweleh (Juni 1991), Cubriya Gawe Cilaka (Juli 1991), Uwuh Gawe Kisruh ( Desember 1991), Thuyul (Januari 1992), Kebacut (Februari 1992), Njagani Tembe Mburi ( Maret 1992), Nggugu Karebe Dhewe (Mei 1992), Keweleh (Juni 1992), Gara-gara Manuk (Agustus 1992), Noleh (September 1992), Nggolek Cukup (Oktober 1992), Kisruh (Desember 1992), Kejodheran (Januari 1993), Serpele Dadi Gawe (Februari 1993), Kelalen (Maret 1993), Wurung (Mei 1993), Kleru Tampa I (Juni 1993), Kleru Tampa II (Juli 1993), Pondhokan Anyar (Agustus 1993), dsb (Dokumen TV RI Stasiun Yogyakarta). Handung KS mulai menulis karya sastra tahun 1959 di Kedaulatan Rakyat. Naskah drama karya-karya Handung KS yang pernah dipentaskan, antara 190 lain: Protes (1977), Keris (1977), Informan (1977), Tamu Agung (1977), Penasaran (1977), Cuwilan 1 Maret (1977), Pahlawan Tanpa Tanda Jasa (1977), Ndara Gaya Baru (1978), Sasi Putih (1978), Loakan (1978), Mripatmu Isih Bening (1978), Bundhet (1978), Jejaka Tuwa (1978), Intimidasi (1978), Tetimbangan (1978), Nyelengi (1979), Layang Wasiyat (1979), Naksir (1979), Ajar Sindhen (1979), Botoh Main (1979), Tamu (1980), Nabok Nyilih Tangan (1980), Kuwe Weke Sapa? (1980), Kekancingan (1980), Aja Dumeh (1980), Bojo (1981), Rusak Bareng (1981), Koruptor (1981), Pungli Dalan Gedhe (1981), Isih jembar Kalangane (1981), Ibu Kuwalon (1982), Klenyit (1982), Susu (1982), Omah Anyar (1982), Wartawan (1982), Ana Urang Neng Mburi Watu (1983), Isin (1983), Aku Manut Mas (1983), Sri Panggung (1983), Cecak (1983), Kumpul Kebo (1984), Dhudha Kesepen (1984), Buta Huruf (1984), Kepuntir (1984), Satriya (1984), Liburan (1985), Ditunggangi (1985), Pelayan Ayu (1985), Lemah Warisan (1985), Lumrah, Seniman (1986), Jago Lurah (1986), Tilas Wong Kunjaran (1986), Tabrak Lari (1987), Turu Awan (1987), Sewengi Neng Warung Kopi (1987), Nyaketi Pemilu (1987), Latihan (1987), Omah Pondhokan (1987), Nggabro (1988), Pokale Pangindhung (1988), Thuyul (1988), Hadiah (1988), Randha (1989), Gudheg Ayu (1989), Main Kertu (1989), dsb. (Dokumentasi naskah Handung KS). Lima naskah Handung Kus Sudyarsana juga diterbitkan, yakni: Isih Jembar Kalangane, Layang Wasiyat, Sasi Putih, Sing Enom lan Sing Tuwa, dan Mripatmu Isih Bening. Kelima naskah tersebut pernah ditayangkan di TVRI Stasiun Yogyakarta dalam serial Sandiwara Jenaka KR Maria Kadarsih (penulis naskah dan sutradara) berusaha mengekspresikan karya-karyanya yang diambil dari masalah sosial kemasyarakatan. Karyakaryanya antara lain: (1) Ngundhuh wohing Pakarti (9 Desember 1984), (2) Kabegjan (20 Jan 1985), (3) Kesaput Mendhung (24 Feb 85), (4) Bibit Kawit (3 Maret 1985), (5) Prahara (17 Agust 85), (6) Pitung Taun Kepungkur (22 Juni 1986), (7) Sungsang (26 Okt 1986), (8) Ninggal Nalar (7 Januari 1987), (9) Nagih Janji (13 April 1987), (10) Omah Warisan (26 Mei 1987) Karya-karya Soemardjono antara lain: (1) Kanyatan Kuwi Kejujuran (siaran 3 Januari 1982), (2) Sing Pecah Entuk Wadhah (21 Maret 1982), (3) 191 Sandhangan lan Kanteban Moral ( 28 Maret 1982), (4) layang-layang sing Misterius (4 April 1982), (5) Tibane Sih Katresnan (19 September 1982), (6) Perjoangan Ancik-ancik Pucuking Eri (17 Desember 1982), (7) Arta Bisa Gawe Mulya, Nanging Uga Bisa Nglengkara ( 23 Oktober 1983), (8) Sopir Gadhungan ( 30 Oktober 1983), (9) Baline Layang-layang Katresnan (6 Nopember 1983), (10) Jariah Njaluk Bali Omah (13 Nopember 1983). DAFTAR PUSTAKA Asmara, Adhy, 1986, Apresiasi Drama, Yogyakarta: Nur Cahaya Bandem, I Made dan Sal Murgiyanto, 1996, cet.IV, Teater Daerah Indonesia, Yogyakarta: Kanisius Becker, AL. 1971. Text Building Epistemology, and Aesthetic in Javanese Shadow Theater. Ann Arbor: Michigan University Dumairy, 1997, “Menanamkan Jiwa Wiraswasta Lewat Drama Jawa-Mahasiswa” Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat Harymawan, RMA, 1993, Dramaturgi, Bandung: Remaja Rosdakarya Hoetomo, Suripan, 1993, “ Drama dalam Sastra Jawa Modern” dalam Poer Adhie Prawoto, ed, Wawasan Sastra Jawa Modern, Bandung: Angkasa Innis, Fenwick Sara (ed.), 1967, A Critical Approach to Children’s Literature, Chicago:University of Chicago Press Kayam, Umar. 1981. Seni, Tradisi, Masyarakat. Jakarta: Sinar Harapan. Koentjaraningrat. 1984. Kebudayaan Jawa. Jakarta: PN Balai Pustaka. Kuntowijoyo, 1984, “Penokohan dan Perwatakan dalam Sastra Indonesia” dalam Andy Zoeltom, ed., Budaya Sastra, Jakarta: CV Rajawali Luxemburg, Jan van, dkk, 1989, Pengantar Ilmu Sastra, Jakarta: Gramedia Mertosedono. Amir. 1992. Wayang dan Sejarahnya. Jakarta: Tiga Aksara Muddjanattistomo, dkk., 1977, Pedhalangan Ngayogyakarta. Jld I. Ngayogyakarta: Yayasan Habirandha Mulyono, Sri, 1978, Wayang: Asal-usul, Filsafat dan Masa Depannya. Jakarta: Gunung Agung 192 __________, 1979. Simbolisme dan Mistikisme dalam Wayang. Jakarta: Gunung Agung Nusantara, Bondan dan Lephen Purwa Raharja, ed., 1997. Ketoprak Orde Baru. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya Oemarjati, Boen. S., 1971, Bentuk Lakon dalam Sastra Indonesia, Djakarta: Gunung Agung Padmopuspito, Asia. tt., Diktat Teori Satra Jawa. Tidak Diterbitkan ________________, 1989, Teori Sastra Jawa, Tidak diterbitkan, Materi kuliah di IKIP Yogyakarta. Padmosoekotjo, tt., Ngengrengan Kasusastran Djawa, Jilid I dan II, Jogjakarta: Hien Hoo Sing Poedjosoedarmo, Soepomo dan Soeprapto Budi santoso. 2000. “Dagelan Mataram: Apresiasi Masyarakat Yogyakarta” dalam Ketika Orang Jawa Nyeni. Heddy Shri Ahimsa Putra, ed. Yogyakarta: Galang Press Poerbatjaraka, 1964, Kapustakan Djawi, Djakarta: Penerbit Djambatan Ras, J.J., 1985, Bunga Rampai Sastra Jawa Mutakhir, Jakarta: Grafitipers Roekijah, R.S., 1958, “Nalusur Bab wontenipun Dedrama-Djawaan Tijang Mlarat”, Dalam Medan Bahasa Djawi, th. III, no. 5, Djakarta: Bagian Bahasa Djawatan Kebudajaan Kementerian PPK. Sahid, Sri Harjanto, 1995, “Kreativitas dan Pengaruh Drama Jawa” Yogyakarta: Makalah dalam Seminar Drama Jawa-Mahasiswa, Pusat Studi Wanita IKIP Yogyakarta, 18 Desember Saleh, Mbijo, 1967, Sandiwara dalam Pendidikan, Djakarta: Gunung Agung Saptono, 1997, “Drama Jawa Menyehatkan Imajinasi Mahasiswa” Jakarta: Kompas, 3 Agustus, hal. 16 Sastroamidjojo, A. Seno, 1964, Renungan tentang Pertundjukan Wajang Kulit, Djakarta: Penerbit PT. Kinta Sedyawati, Edi, dkk, Editor, 2001, Sastra Jawa: Suatu Tinjauan Umum, Jakarta: Balai Pustaka Seto, Kak, 1995, “ Mendrama Jawa dan Kreativitas Mahasiswa” Yogyakarta: Makalah dalam Seminar Drama Jawa-Mahasiswa, Pusat Studi Wanita IKIP Yogyakarta, 18 Desember 193 Soebadyo, Haryati, 2002, Indonesian Heritage: Bahasa dan Sastra, Jakarta: Buku Antar Bangsa, jilid 8 dan 10 Soedarsono, 1986, “Dampak Modernisasi terhadap Seni Pertunjukan Jawa di Pedesaan”, dalam Soedarsono, ed., Kesenian, Bahasa, dan Folklor Jawa, Yogyakarta: Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara (Javanologi) Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan __________, 1997, Wayang Wong: Drama Tari Ritual Kenegaraan di Keraton Yogyakarta, Yogyakarta: Gadjahmada University Press Soemardjono, 1987. “Pengolahan Lakon dan Penyutradaraan” dalam Bidang Kesenian Kanwil Depdikbud DIY. Ed.. Tuntunan Seni Kethoprak. Yogyakarta: Proyek Pengembangan Kesenian Depdikbud DIY Sopingi, 1998, “Peningkatan Peran Drama Jawa untuk Pembentukan Budi Pekerti Mahasiswa” , Makalah dalam Saresehan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta Sriyono, Bambang. 1983. “Wayang Wong Kolosal dan Langendriyan versi Ensiklopedi”. Kompas Minggu, Jakarta. 16 Oktober 1983. Suardiman, 1952 ………. Suarsa, Made, 1988, Drama-drama B. Sularto, Analisis Strukturalisme Semiotik (Tesis Pasca Sarjana UGM, belum diterbitkan) Subalidinata, R.S., 1981, Seluk Beluk Kesastraan Jawa, Yogyakarta: KMSN Fakultas Sastra dan Kebudayaan, UGM ______________, 1985, Primbon dalam Kehidupan Masyarakat Jawa: Unsur Sastra, mithos, takhayul dan sejarahnya, Makalah pada ceramah di Javanologi, Yogyakarta: Depdikbud Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara, bulan April 1985. Sudjiman, Panuti, 1986, Kamus Istilah Sastra, Jakarta: Gramedia Suharto, Ben, dkk., 1999, Langen Mandra Wanara, Sebuah Opera Jawa, Yogyakarta: yayasan Untuk Indonesia Sumardjo, Jakob, 1992, Perkembangan Teater Modern dan Sastra Drama Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 194 Suseno, Frans Magnis, 1982. Kita dan Wayang. Jakarta: Lembaga Penunjang Pembangunan Nasional. Sutandyo, 2002, Kamus Istilah Karawitan, Jakarta: Wedhatama Widya Sastra Tambayong, Japi, 1981, Dasar-dasar Dramaturgi, Bandung: Pustaka Prima Tarigan, Henry Guntur, 1985, Prinsip-prinsip Dasar Sastra, Bandung: Penerbit Angkasa Taylor, Loren E. 1981, Drama Formal dan Teater Remaja, Terjemahan A.J. Soetrisman, Yogyakarta: Yayasan Taman Bina Siswa Teeuw, A., 1984, Sastra dan Ilmu Sastra: Pengantar Teori Sastra, Jakarta: Pustaka Jaya Wellek, Rene & Austin Warren, 1993, Teori Kesusasteraan, Diindonesiakan oleh Melani Budianta, Jakarta: Gramedia Wibisono, Singgih, 1987, “Konvensi dan Invensi dalam Sastra Pedalangan”, dalam Gatra, Majalah Warta Wayang, No. 16. Jakarta: Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia) Zoetmulder, 1983, Kalangwan: Sastra Jawa Kuno Selayang Pandang, Jakarta: Djambatan 195 Baca kebudayaan Jawa hal 211 KONTRIBUSI KONSEP SENI TEATER TERHADAP PERKEMBANGAN SENI PEWAYANGAN Soediro Satoto I Setelah saya konfirmasikan kepada panitia, judul makalah ini saya terima dan gunakan sesuai dengan permintaan DPH SENA WANGI (Dewan Pimpinan Harian SEKRETARIAT NASIONAL PEWAYANGAN NASIONAL). Ada kesan (mudah-mudahan tidak benar) bahwa wayang bukan teater sehingga konsep seni teater diharapkan bisa memberi kontribusi terhadap perkembangan seni pewayangan. Ada yang berpendapat bahwa "Seni Pewayangan bukan Seni Teater". Maka, konvensi, metode, dan pendekatan untuk mengkaji dan menggarap Seni Pewayangan harus dibedakan dengan konvensi, metode, dan pendekatan untuk mengkaji, dan menggarap Seni Teater. Pendapat tersebut sah-sah saja. Sama sahnya dengan pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa Seni Drama bukan Seni Teater, tetapi Seni Sastra. Pengkajian atau penelitian terhadap Seni Teater berada di luar konvensi dan pendekatan sastra, melainkan berada dalam wilayah kajian seni – Lalu seni yang mana? Bukankah sastra, termasuk drama, juga seni, seni sastra? Ada yang berpendapat bahwa Seni Drama dan Seni Teater termasuk bidang Seni Rupa. Sedangkan orang lain berpendapat bahwa Seni Rupa termasuk bidang Seni Arsitekstur. Ada kesan bahwa Seni Pewayangan disejajarkan atau disamakan dengan Seni Pedalangan, sehingga di beberapa Perguruan Tinggi Seni menggunakan nama Jurusan Pedalangan, bukan Jurusan Pewayangan. Pendapatpendapat tersebut seharusnya didukung oleh alasan-alasan dan konsep-konsep yang jelas, dan jelas pula acuannya sehingga tidak menimbulkan kerancuan dan kekaburan. Dalam makalah ini, Seni Pewayangan dimasukkan sebagai seni pertunjukan. Ia adalah Seni Teater, ‘Seni Teater Tradisional’ yang akan selalu mengalami reformasi dan tranformasi seperti halnya seni-seni tradisional yang lain, dan juga seni-seni kontemporer, termasuk ‘Seni Teater Kontemporer’. Seni Tradisional bukan seni yang telah mandeg, baku, dan beku. Ia terus mengalami perkembangan atau bahkan perubahan seirama dengan transformasi di segala bidang, tanpa kecuali bidang budaya dan seni, khususnya Seni Pewayangan atau Seni Pedalangan. Namun sebaliknya, seni tradisi bisa memperkaya seni modern (lihat Rendra 1983:3). Dengan demikian, konsep Seni Teater bukan hanya bisa memberi kontribusi terhadap perkembangan Seni Pewayangan, tetapi juga dapat dicobaterapkan ke dalamnya. II 196 Seni Teater adalah produk sebuah proses penciptaan dari seni drama ke dalam seni teater, atau dapat disingkat ‘proses teater’. Sebagai proses teater, keberadaan Seni Teater mengacu pada ‘formula dramaturgi’. Istilah ‘dramaturgi’ itu sendiri dipungut dari bahasa Belanda ‘dramaturgie’, berarti ajaran tentang seni drama (leer van de dramatische kunst), atau dari bahasa Inggris ‘dramaturgy’, berarti seni atau teknik penulisan drama dan penyajiannya dalam bentuk teater. Secara singkat bisa disebut ‘seni teater’ (the art of the theatre) (Harymawan 1988:iii). Safian Hussain dkk. dalam Glosari Istilah Kesusasteraan (1988:69) menyebutkan bahwa ‘dramaturgi’ adalah komposisi dramatik atau seni dramatik, yaitu unsur-unsur teknikal yang digunakan dalam penulisan drama. Unsur bunyi dan unsur lakuan atau gerak merupakan dua unsur penting di antara unsur-unsur penting lainnya dalam drama. Dan inilah yang membedakan antara teknik penulisan drama atau lakon dengan jenis sastra yang lain, yaitu prosa (novel atau cerpen) dan puisi. Pendekatan dramaturgi (approache dramaturgique), yang di Perancis dipelopori dan dikembangkan oleh Jacques Scherer, bertujuan untuk menjelaskan bagaimana seorang pengarang drama menggunakan kerangka bentuk tertentu serta prosedur tertentu dalam mengarang (Scherer 1980:5, dalam Bachmid 1990:26). Yang dimaksud rumusan atau ‘formula dramaturgi’ di atas merupakan proses (penjadian) teater yang meliputi 4M, yaitu (1) Mengchayal (dalam bentuk ide); (2) Mencipta atau Menuliskan (dalam bentuk dramatic script, teks dramatik, atau naskah lakon); (3) Mempertunjukkan atau Mempergelarkan (dalam bentuk teks pertunjukan atau seni teater); dan (4) Menyaksikan, Menonton (bisa dalam bentuk komentar, ulasan, resensi, kritik, kajian, atau penelitian). Perbedaan istilah ‘drama’ dan ‘teater’, sebagai proses kreatif seni, dapat dilihat pada pasangan ciri-ciri berikut (lihat Tennyson 1967:1; Satoto 1991:6—25). drama teater, pergelaran wayang play (lakon, sandiwara) performance (pertunjukan, pergelaran) script (naskah, bisa bentuk sketsa) production (produksi) dramatic text (teks dramatik) perfomance text (teks pertunjukan) author (pengarang) direction (sutradara, dalang) caracter (tokoh) aktor/aktris, boneka wayang (dimainkan oleh dalang) creation (kreasi) interpretation (interpretasi, oleh dalang) theory (teori) implementation (implementasi) Berdasarkan perbandingan di atas, tampak bahwa (1) drama lebih merupakan lakon yang belum dipentaskan; (2) skrip atau naskah lakon (apa pun wujudnya) yang belum diproduksikan; (3) teks dramatik yang masih harus memperoleh tingkat kesempurnaannya di dalam teks pertunjukan, sehingga segala jenis seni 197 pertunjukan harus konteks dengan publiknya (audience); (4) hasil kreasi, ide, atau gagasan pengarang (dalam naskah lakon) yang dalam batas-batas tertentu masih harus diinterpretasikan oleh sutradara (dalang) beserta seluruh pekerja teater untuk mementaskannya; (5) tokoh dalam teks dramatik, atau aktor dalam teks pertunjukan yang masih kosong harus memperoleh fungsi dan peran (oleh sutradara atau dalang) sehingga setiap tokoh dalam setiap lakon memiliki karakteristiknya masing-masing. III Kini, baik secara konsepsional, apalagi jika dilihat dari wujud atau bentuk, gaya, penggarapan, dan atau pementasannya, kita semakin sulit membedakan dan memberi batasan mana karya seni yang paling berhak meng-claim atau disebut teater klasik, teater tradisional, teater rakyat, teater daerah, teater lokal, teater nasional, teater Indonesia, teater Barat, teater modern, atau teater kontemporer. Hal itu terjadi karena jenis-jenis teater tersebut sama-sama mengalami perkembangan dan atau perubahan paradigma seirama dengan transformasi dan globalisasi budaya dan seni. Teater modern dan teater kontemporer yang sebagian orang menengarai dengan masuknya konvensi (dari) Barat, antara lain konvensi adanya naskah lakon tertulis; sementara teater tradisional tidak menggunakannya. Mana pula yang disebut seni adiluhung, yang konon, harus dilestarikan (apanya?). Sementara tata nilai itu sendiri terus mengalami perkembangan dan atau perubahan. Wayang Kulit Purwa Jawa, misalnya, sering disebut jenis teater tradisional adiluhung yang harus dilestarikan (apanya: filosofinya, fungsinya, konvensinya, wujud bonekanya, bentuk, garap, atau gaya pergelarannya, atau semuanya?). Jika semua itu benar, maka seni pewayangan telah mengingkari hakikat seni itu sendiri yaitu bersifat kreatif dan inovatif. Di wilayah Indonesia, kita kenal berbagai jenis seni teater yang lazim disebut ‘teater tradisional’ (telah mentradisi), ‘teater rakyat’ (karena merakyat); atau ‘teater daerah’ (berciri khas daerah). Secara konvensional, yang dimaksud teater daerah terbatas pada seni pertunjukan yang memiliki ciri khas daerah tertentu. Jenis teater yang tidak berciri kedaerahan adalah teater Barat. Perbedaan utama antara teater Barat dan teater daerah Indonesia adalah selalu adanya naskah lakon tertulis dalam produksi teater Barat (Bandem & Murgiyanto, 1996:10). Perlu dipertanyakan tentang ciri khas daerah tertentu yang mana? Bahasanya, gayanya, garapnya, apa geografisnya? Begitu pula, dalam kenyataannya sekarang, ada teater modern yang diasumsikan teater Barat tetapi tidak menggunakan naskah lakon tertulis, melainkan dengan improvisasi-improvisasi dan kata-kata mini atau sketsa, yang biasa disebut teater mini kata atau teater primitif. Misalnya, lakon Bib Bob (Rendra), dan lakon RE (Akhudiat). Sebaliknya, ada teater daerah yang menggunakan naskah lakon tertulis, dan digarap berdasarkan konvensi Barat. Misalnya Kethoprak Glinding di Solo; kethoprak, wayang orang, atau wayang kulit yang dipentaskan dan/atau ditayangkan di teve, atau dipentaskan ‘dalam rangka’. Contoh-contoh lain adalah seni-seni tradisional yang semangatnya adalah eksperimental atau eksplorasi. Apa salahnya jika teater daerah atau teater tradisional jenis wayang memanfaatkan naskah lakon tertulis, diterjemahkan atau tidak ke dalam bahasa nondaerah, dan digarap berdasarkan konvensi teater 198 (diasumsikan Barat?). Peristiwa demikian sering juga dilakukan bagi teater Barat yang diterjemahkan ke dalam bahasa daerah di Indonesia, digarap berdasarkan konvensi, gaya, dan bentuk-bentuk, atau roh teater daerah di Indonesia. Jadi, ciriciri kedaerahan (termasuk bahasa daerah), naskah lakon tertulis, dan konvensi yang dipakai, dalam perkembangannya sekarang, tidak cukup akurat sebagai pembeda antara Teater Daerah (di Indonesia), dan Teater Barat (tidak selalu sama dengan non-Indonesia), atau Teater Tradisional dan Teater Modern. Beberapa contoh jenis teater rakyat, teater daerah, atau teater tradisional di Indonesia adalah: Bangsawan (Sumatra Utara); Randai (Sumatra Barat); Dermuluk (Sumatra Selatan); Makyong, Mendu (Riau, Kalimantan Barat); Mamanda (Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur); Ubrug, Longser, Bonjet (Jawa Barat); Lenong, Topeng, Blantik (Batawi); Mansres (Indramayu); Sintren (Cirebon); Kethoprak (Yogya, Solo, Jawa Tengah, Jawa Timur); Wayang (Kulit atau Purwa, Orang, Topeng, Golek, Sungging, Gedog, Kidang Kencana, Menak; Klitik atau Krucil, Kulit Perjuangan, Kulit Kancil, Potehi, Cina, atau Thithi, Beber, Madya, Tasripin, Suluh, Wahana, Pancasila, Wahyu) tersebar hampir di seluruh Jawa; Dadung Awuk (Yogya); Kuda Lumping (Yogya, Solo, Jawa Tengah, Ponorogo, Jawa Timur); Srandul (Jawa Tengah, Jawa Timur); Ludrug, Kentrung (Jawa Timur); Drama Gong, Gambuh, Arja, Topeng, Prembon (Bali); Topeng Dalang (Klaten, Jawa Tengah, Jawa Timur); Topeng (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Madura); Panji (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur) (Satoto 1991:121—189). Berdasarkan contoh-contoh di atas, jelas bahwa seni teater wayang memiliki jenis paling banyak daripada yang dimiliki oleh seni teater tradisional lainnya. Jumlah jenis teater wayang dan pengelompokannya setiap pengamat bisa saja berbeda. Kesamaanya, jenis-jenis teater wayang tersebut, masing-masing, memiliki spesifikasi dan karakteristiknya sendiri. Jenis dan ragam teater wayang itu masih akan terus berkembang dan bertambah jumlahnya. IV Mengapa jenis dan ragam seni pewayangan masih terus mengalami perkembangan, bahkan perubahan, baik secara kuantitas maupun kualitas seninya jika dilihat dari segi wawasan seniman wayang yang bersangkutan, konvensi, metode, pendekatan, gaya, dan teknik penggarapan yang digunakan dalam proses pementasan wayang yang dihehendaki. Jika proses perkembangan wayang akan terus berlangsung tanpa hambatan, apa lagi ancaman atau sanksi, maka hal itu mengindikasikan bahwa (1) Seni Pewayangan, termasuk Seni Pedalangan (Seni Penyutradaraan Plus), Seni Karawitan/Musik (tata musik atau suara), dan Seni Tari (tata gerak atau lakuan) yang secara konvensional merupakan komponenkomponen utama di samping komponen-komponen penting lainnya yang membangun komunitas Seni Pewayangan, bukanlah seni tradisional yang mandek, statis, baku, dan beku, melainkan dinamis seirama dengan perkembangan dan dinamika masyarakat wayang sebagai publiknya, tanpa harus mengorbankan esensi Seni Pewayangan; (2) Para pecinta dan pemerhati wayang, pengayom wayang, pengelola wayang, pemikir wayang, kritikus wayang, peneliti wayang, dan masyarakat wayang pada umumnya sebagai publiknya, bukanlah 199 orang-orang tradisional yang fanatik akan kemapanan, sementara seniman wayang generasi penerusnya merasa resah dan gelisah terhadap kemapanan.tersebut. Slamet Gundono, S.Kar., misalnya, dalang muda nan tambun lepasan STSI Surakarta, merasa resah dan gelisah melihat ikatan ketat kemapanan tradisi, pakem-pakem yang membelenggu kreativitas seninya (sanggit). Ia mencobaterapkan konvensi-konvensi seni teater yang pernah diterimanya, digaulinya, dan dihayatinya ke dalam pementasan Wayang Suketnya. Bonekaboneka Wayang Kulit Purwa yang memiliki makna simbolis dan karakteristik baku, hitam putih diganti dengan boneka-boneka dari suket (rumput, atau mendong) yang secara simbolis dapat dimaknai kesederhanaan.Tokoh yang menghadapi Karna untuk mengklarifikasikan sikap Karna terhadap Pandawa, khususnya Ibu Kunthi pada Perang Bharatayudha, tidak harus Kresna dan Harjuna, melainkan bisa Werkudara. Secara logika lebih masuk akal karena Werkudara bukan tak mungkin menjadi peragu atau dendam karena kematian Gatutkaca akibat senjata Kunta Wijaya Danu yang dilepaskan Karna, kakak kandung Werkudara sendiri, seibu dengan Ibu Kunthi. Tampilnya dunia fiksi dan nonfiksi dalam struktur Wayang Suket Gundono terasa lebih teatrikal dan artistik daripada adegan Limbukan dan Goro-Goro beberapa dalang akhir-akhir ini yang menjadi arena pemujaan berlebih-lebihan terhadap penanggap atau yang mensponsori pendanaan pergelarannya, sebaliknya justru terjadi pelecehan terhadap para pekerja teater wayang, dan pilihan pendengar, demi merebut pangsa pasar. Contoh lain, pementasan Wayang Nggremeng Gundono dalam Alap-alapan Surtikanthi sebuah lakon karya Goenawan Mohamad. Tidak ada boneka wayang, tidak ada gamelan (tradisional). Gundono bukan dalang otoriter dan penafsir tunggal seperti lazimnya pergelaran Wayang Kulit Purwa. Seluruh pekerja teater Wayang Nggremeng bisa menafsirkan lakon sesuai dengan wawasan dan daya apresiasi masing-masing. Dengan demikian, makna lakon, sebagai karya fiksi, bisa memiliki berbagai penafsiran seperti apa yang dikemukakan dalam teori dekonstruksi atau pascamodernisme (Culler 1983). Seluruh pekerja teater Wayang Nggremeng juga berperan sebagai pemain, peniru suara gamelan (pengrawit), bahkan sebagai dalang sekalipun. Mereka bisa santai makan, minum, merokok, dan bercanda tentang hal-hal yang aktual dan konteks dengan kondisi sosial, politik, ekonomi, hukum, dan hankam yang sedang menjadi isu aktual. Makanan, minuman, dan rokok berserakan di hadapan para pemain, siap dijadikan peraga atau boneka wayangnya. Gundono mengikuti jejak gurunya Gondo, bahwa cerita wayang sebagai karya fiksi bisa divisualisasikan secara nonfiksi, ditafsirkan, atau dimaknai bermacam-macam, bahkan tafsir atau makna gila-gilaan sekalipun (posmodernisme). V Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kontribusi dan implementasi konsep seni teater terhadap perkembangan seni pewayangan bisa menyangkut di bawah ini. 200 Pertama, struktur teatrikalnya, misalnya komponen dalang dan seni pedalangan (sutradara dan teknik penyutradaraan); karakter (tokoh), teknik penokohan, pemeran dan teknik pemeranan (pada wayang kulit dilakukan oleh dalang berupa sabet dan cakapan); dialog (cakapan, pada wayang orang dilakukan oleh pemeran); struktur ruang (pada wayang kulit, gedebog dan kelir lambang mikro dan makrokosmos), dan struktur waktu (pathet, pengaluran, dan pengadegan); mempotensikan seluruh pekerja teater wayang secara profesional dan proporsional (niyaga atau penabuh gamelan, wirasuara, penata panggung, penata suara, penata lampu, penata properti atau perlengkapan, dan lain-lain) sehingga kreativitas mereka bisa dihargai secara profesional dan proporsional berdasarkan hasil karya kolektif mereka bersama dalang, artinya tidak sekadar memperoleh upah dari Sang Dalang. Kedua, masalah penafsiran lakon, sanggit, dan teknik pemanggungan. Dalang bukan satu-satunya sumber penafsir dan pencipta lakon, melainkan juga seluruh pekerja teater wayang. Untuk keperluan ini, di samping dalang, setiap pekerja teater wayang perlu selalu meningkatkan wawasan, daya apresiasi, dan daya kreativitasnya terhadap Seni Pewayangan dan Seni Pedalangan sebagai karya seni kolektif. Ketiga, perlu pengkajian dan penelitian terus-menerus terhadap masyarakat wayang (termasuk penonton, pemerhati, pengamat, kritikus, peneliti, dan pengayom) sebagai publiknya, karena perkembangannya cenderung semakin heterogen. Keempat, masalah manajemen seni pertunjukan, terutama manajemen seni tradisional, dalam hal ini pergelaran wayang kulit purwa Jawa, umumnya masih merupakan industri atau perusahaan perseorangan di mana Dalang sebagai pemilik modal tunggal dan pemimpin tunggal sebagai majikan yang memiliki otoritas tunggal. Sedangkan para pekerja (crew) teater wayang kulit merupakan buruh-buruhnya. Kondisi demikian bisa dikaji ulang, dilakukan penelitian, dan dicarikan solusi terbaiknya sehingga menguntungkan semua pihak yang terkait dengan pergelaran wayang kulit purwa Jawa tersebut sebagai suatu karya seni kolektif dan kompleks secara proporsional dan profesional.. Kelima, dirasa perlu, penting, dan mendesak segera dicari dan ditemukan konsep atau teori seni pewayangan atau seni pedalangan, khususnya teknik penggarapan dan atau gaya pementasan wayang, demi perkembangan dan pengembangan seni pewayangan itu sendiri. Keenam, kritik seni, khususnya kritik seni pewayangan dan/atau seni pedalangan, bukan saja perlu dilembagakan, tetapi juga perlu mendapat porsi dan kesempatan yang layak untuk melakukan kritik sesuai dengan kompetensi kritikus, serta hakikat, arti, dan fungsi kritik. DAFTARPUSTAKA Bachmid, Talha, 1990. Semangat ‘Dérision’ dalam Drama Kontemporer: Telaah Bandingan Dua Lakon "Kapai-Kapai" Karya arifin C Noer dan "Badak-Badak" 201 Karya Eugène Ionesco. Disertasi. Fakultas Pascasarjana UI Jakarta. Belum diterbitkan. Bandem, I Made & Sal Murgiyanto. 1996. Teater Daerah Indonesia. Jakarta: Pustaka Budaya. Culler, Jonathan. 1983. Theory and Criticism after Structuralism. London, Melbourne and Henley: Routledge & Kegan Paul. Harymawan, RMA. 1988. Dramaturgi. Bandung: CV Rosda. Hussain, Safian dkk., 1996. Glosari Istilah Kesusastraan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kemerdekaan Pendidikan Malaysia. Rendra. 1983. Mempertimbangkan Tradisi. Jakarta: PT Gramedia. Satoto, Soediro. 1991a. Pengkajian Drama I. Surakarta: Sebelas Maret University Press. _____________ 1991b. Pengkajian Drama II. Surakarta: Sebelas Maret University Press. _____________ 1984. Wayang Kulit Purwa: Makna dan Struktur Dramatiknya. Penelitian. Yogyakarta: Proyek Javanologi Depdikbud RI. ______________ 1998. Tokoh dan Penokohan dalam Caturlogi Drama "Orkes Madun" Karya Arifin C Noer. Disertasi. Program Pascasarjana UI Jakarta. Akan diterbitkan. ______________ 1999a. Teater Indonesia. Makalah. Disajikan dalam Forum Simposium Nasional. Dalam rangka Festival dan Temu Ilmiah MSPI 1999 pada tanggal 09—14 September 1999, di Tirtagangga Karangasem Bali. _______________ 1999b. Mencari Format Pedalangan Era Reformasi. Dimuat di SOLOPOS pada tanggal 30 September 1999, Halaman 4. · DR. H. Soediro Satoto Kepada Yang Terhormat Fak. Sastra & Program Pascasarjana UNS Jl. Ir. Sutami 36 A Sekretariat SENA WANGI Kentingan, Surakarta, 57126 Gedung Pewayangan Kautaman Jl. Giringan 03 Jl. Raya Pintu Satu, TMII Kartasura, 57167 Surakarta Jakarta Timur 13810 Jenis primbon merupakan hasil dari penulisan tradisi sastra atau budaya lisan. Kata primbon sendiri berasal dari kata dasar (lingga) imbu dan berarti ‘simpanan’, yakni simpanan yang berupa sastra atau budaya lisan yang telah 202 dihayati atau dipraktikkan oleh masyarakat Jawa secara turun temurun dari generasi satu ke generasi berikutnya. Dalam hubungannya dengan beberapa hal di atas, suatu ketika Umar Kayam (1981: 95-96) dalam mencermati tiga macam teater kota, berkesimpulan sebagai berikut. Pertama, kenyataan bahwa teater yang berorientasi pada nilainilai budaya yang sudah akrab dengan masyarakat adalah teater yang lebih mudah menemukan format khalayaknya. Dalam hal ini agaknya penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar masih merupakan faktor yang penting (Ketika itu dan entah sampai kapan, tergantung masyarakatnya). Kedua, kenyataan bahwa teater yang mampu menggalang khalayak dalam jumlah tetap yang besar adalah teater yang “dikemas” secara komersial. Dengan lain perkataan, teater kitsch, yakni teater yang berorientasi pada kemungkinan perkembangan menjadi “seni massa” yang secara komersial menguntungkan. Teater yang sejak semula dikemas untuk dijajakkan secara komersial dengan seluwes mungkin menyesuaikan diri pada selera massa dengan tujuan bisa dicapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Ketiga, kenyataan bahwa teater yang memilih alternatif lain dari pada tersebut di atas akan merupakan “teater minoritas” yang akan mempunyai format dan khalayaknya yang kecil. Pengembangan makna dari kondisi yang melatar-belakangi adalah inovasi pada masing-masing cerita yang bersangkutan. Pembicaraan tentang korupsi yang dilakukan oleh tokoh Limbuk dan Cangik dalam adegan Limbukan, misalnya, merupakan inovasi yang memang mungkin terjadi dalam hubungannya dengan masyarakat tertentu pada waktu tertentu. Hanya dengan menengok pada latar belakang masing-masing situasi budaya masyarakatnya itulah pemaknaan drama Jawa pada masing-masing jenis, bahkan pada masing-masing lakon, setidak-tidaknya akan terdasari. Sebaliknya, benang merah idealisme filosofis yang dapat ditarik dari budaya animisme-dinamisme, pengaruh budaya Hindu-Budha, pengaruh budaya 203 Islam, dan pengaruh budaya modern Barat, akan merupakan idealisme budaya Jawa yang lestari yang mungkin juga tercermin dalam setiap jenis drama, bahkan setiap teks drama Jawa, baik yang konvensional maupun yang inovatif. Berbagai makna drama Jawa yang inovatif yang keluar dari jalur benang merah di atas, bisa dipastikan bersifat subyektif dan kemungkinan sekali akan punah ditelan waktu. 204