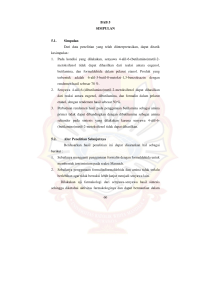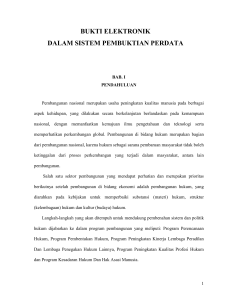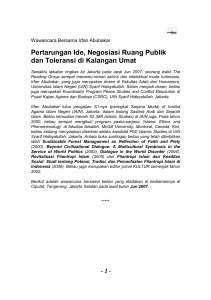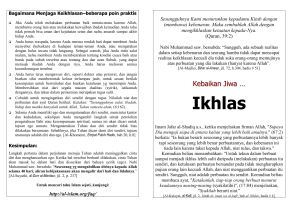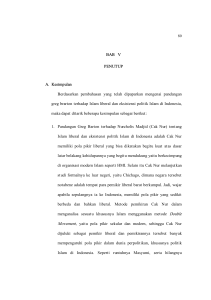ISLAM LIBERAL, Kritik pada Kritisisme 'Kenakalan' Abdul ‘Dubbun’ Hakim Pada Maret 2007 nanti Jaringan Islam Liberal alias JIL genap berusia enam tahun. Sebuah usia yang masih sangat muda untuk perjalanan suatu pemikiran, meski mendapat sambutan yang sangat luas di khalayak publik Islam (di) Indonesia. Respons publik terhadap gagasan yang dilontarkan JIL selama ini dapat dibaca sebagai sebuah prestasi yang sangat mengagumkan untuk perjalanan sebuah pemikiran dengan segala kontroversi yang mengikutinya. Dari sekian respons balik yang ditujukan terhadap pemikiran yang diusung oleh JIL selama ini—sebagaimana yang tercermin di media massa, diskusi publik, bahkan sekadar gosip di sekitarnya—ternyata tidak secara tajam mampu menelisik kerangka bangunan pikiran yang menopang dan mengukuhkan klaim-klaim JIL atas pembaruan Islam. Diskusi dan kontroversi di sekitarnya masih jauh dari iklim pertukaran gagasan yang kritis dan bernas. Perangkap tekstualisme Para eksponen JIL secara umum mengajukan kritik terhadap beberapa kelompok dalam Islam yang antipembaruan menampik keragaman tafsir, historisitas teks-teks suci, universalisme Islam, emoh terhadap sekularisme, dan antiliberalisme. Dengan kata lain, kelompok antipembaruan terperangkap dalam literalisme, lalu menutup kemungkinan kreativitas tafsir. Literalisme sebagai biang keladi radikalisme dan konservatisme pemikiran juga tak sepenuhnya benar. Benarkah ada literalisme dalam pemahaman keagamaan? Pertanyaan ini patut diajukan untuk menguji dan menelusuri kekeliruan pandangan mengenai apa yang disebut literalisme dalam tafsir-tafsir keagamaan, terutama Islam. Literalisme sering diasosiasikan dengan ikhtiar pemahaman keagamaan yang mengklaim sepersis mungkin makna sebuah teks. Dalam literalisme seakan ada korespondensi antara teks dan makna yang dihasilkannya. Kepercayaan pada makna literal sebuah teks bersumber dari pemilahan antara yang literal dan yang metaforis dalam bahasa. Asumsi mengenai bahasa literal dan metaforis diturunkan berdasarkan dualisme metafisis mengenai dunia intelligible dan sensible dalam filsafat bahasa. Dalam kenyataannya, pemilahan ini ditetapkan secara arbitrer; seakan ada makna murni dan makna tidak murni dari bahasa. Sebaliknya, bahasa tidak pernah transparan pada dirinya. Bahasa diwarnai oleh antinomi, heterodoks, bahkan terkontaminasi. Selalu ada jarak antara tanda dan penanda, konsep dan realitas, bahasa dan makna. Tidak ada hubungan yang alamiah antara bahasa dan makna, sebagaimana selalu ada jarak antara konsep dan kenyataan. Tidak ada substansi, stabilitas, stasiun tetap, bahkan posisi dalam kerangka bahasa, baik kelisanan maupun keberaksaraan, apalagi literalisme. Dengan demikian, saya menganggap istilah "literalisme" , "skripturalisme", dan seterusnya adalah problematik dalam kerangka hermeneutika sebagaimana sering diungkapkan JIL. Dalam perjumpaan dengan para pengkritiknya, JIL selalu mengutarakan tafsir tandingan yang dianggap benar, atau sekurang-kurangnya mendekati kebenaran. Bukankah strategi ini terperangkap dalam monisme yang sama, yaitu tekstualisme. Perangkap tekstualisme ini menunjukkan kelemahan mendasar metodologi hermeneutika JIL. Maka, kita sering menyaksikan parade klaim kebenaran tafsir dalam perdebatan JIL dengan para pengkritiknya di panggung-panggung seminar, juga di media massa. Parade klaim kebenaran ini memunculkan politics of nemesis, yaitu politik permusuhan, pembalasan, dan antipati dari lawan-lawannya. Apa yang ditampilkan JIL dalam wilayah tafsir lebih bermuatan dan menonjolkan "kenakalan intelektual" ketimbang usaha serius merekonstruksi pemikiran Islam yang berjejaring dengan kenyataan, atau sebagai respons kritis terhadap dinamika perubahan yang seharusnya diantisipasi oleh umat Islam di hari kini. Rekonstruksi atas Islam dalam posisinya yang dilematis berhadapan dengan kemodernan dan keindonesiaan, seperti yang dilakukan Cak Nur dan eksponen pembaru Islam di awal tahun 1970-an hingga akhir 1990-an, memiliki semangat dan watak yang berbeda dengan eksponen JIL saat ini. Modernitas Negatif Apa yang dialami umat Islam di hari kini sesungguhnya lebih mencerminkan suatu ambiguitas dalam berhadapan dengan modernitas Barat. Di dunia Barat, modernitas merupakan konsekuensi logis sekularisasi yang telah dirintis oleh para pembela Pencerahan. Sejarah Barat, sebagaimana pernah dikemukakan oleh Jacques Derrida, memang diwarnai luka terhadap segala dominasi otoritas keagamaan, sehingga membuahkan maklumat "kematian Tuhan". Adapun sejarah Islam dan Judaisme sama sekali berbeda dengan apa yang mendera Kristiantisme Barat. Baik Judaisme maupun Islam—dengan segala kontroversi di jantung teologinya—tidak pernah berbuah ateisme, apalagi nihilisme. Pertikaian tafsir di dalam sejarah Islam malah dilegitimasi sebagai berkah, bukan bencana. Lalu, di manakah pangkal soalnya? Di dunia Barat yang Kristiani, sekularisasi yang melahirkan modernisme, memberi penghargaan pada otonomi, subyektivitas, dan kritisisme yang memberi ruang bagi perkembangan sains sehingga meraih pencapaian yang menakjubkan. Sementara respek pada kebebasan membuka kemungkinan bagi kesetaraan warga negara dalam konteks negara-bangsa konstitusional modern. Dalam konteks ini kita melihat paralelisme antara sekularisasi, modernitas, dan kebebasan. Sebaliknya, paralelisme itu tidak terjadi terhadap dunia Islam. Modernisasi dengan segala ikon yang termuat di dalamnya dialami secara negatif. Tidak sebagaimana dialami dunia Barat, dunia Islam memasuki modernitas dengan segala atributnya: nasionalisme, demokrasi, kapitalisme, dan tekno-sains justru sebagai imposisi dari luar. Formasi negarabangsa dengan nasionalisme sebagai ideologi perlawanan di dunia Islam sering jadi retorika politik kaum elite untuk bertindak otoriter dan despotik. Demokrasi pun berlangsung tanpa disertai perluasan basis-basis produksi di tingkat massa, kapitalisme malah menjadi momok bagi kaum miskin. Tapi, tragisnya kita menjadi konsumen setia hasil perkembangan tekno-sains modern. Maka, modernitas pada akhirnya berbuah kutuk, bukannya berkah. Bertolak dari kenyataan ini pula, apa yang disebut "pembaruan" oleh JIL dengan mendesakkan kebebasan tafsir atas teks-teks suci hanya berhenti di wilayah hermeneutika. JIL mungkin tampil menjadi salah satu varian tafsir atas Islam, tapi tidak berdaya menghadapi realitas material masyarakat yang masih bergulat dengan problem kesenjangan atau kegagalan negara merealisasikan cita-cita kesejahteraan dan keadilan. Rasio dan komitmen sejarah Membaca realitas yang 'centang-perenang' dengan mendedahkan kebebasan tafsir sungguh bukan jalan keluar yang meyakinkan. Pada level diskursus teologis, JIL berjasa dengan tetap mempertahankan posisi akal budi di hadapan teks-teks suci. Namun, pada level praksis, ikhtiar JIL itu tak berbunyi apa- apa. Hanya menghantam langit kosong sejarah: sejarah pertarungan menegakkan keadilan dan melawan pemiskinan struktural. Kekuatan sebuah pemikiran bukan hanya harus memenuhi syarat koherensi, metode, dan teoritik tertentu, tetapi juga kesanggupannya mengungkapkan kontradiksi, negativitas, dan diagnosa terhadap distorsi-distorsi kekuasaan yang terus berlangsung. Kekuatan sebuah pemikiran, juga pemikiran keagamaan, terletak pada kemampuannya untuk mempertalikan teori dan krisis obyektif yang berlangsung dalam sejarah masyarakat. Khazanah pemikiran berhenti sebagai idealisme ketika tidak berjejak pada kondisi sosial-historis masyarakat, dan krisis-krisis yang menyertainya. Rasio tidak beroperasi di luar sejarah, tapi justru merealisasikan diri dalam mengatasi rintangan diri dalam dan melalui sejarah. Di sisi lain, kaum liberal memahami kebebasan sebagai ketiadaan intervensi dan dimengerti sebagai otonomi yang sepenuhnya individualistik. Gagasan mengenai kebebasan yang diusung kaum liberal ini merupakan konsep yang diwariskan kaum borjuis mengenai otonomi diri. Fiksi mengenai otonomi diri ini mengabaikan kenyataan investigasi secara mendalam mengapa seseorang menetapkan atau memutuskan pilihannya. Rasio dengan komitmen pada perbaikan "kehidupan politis" yang lebih sehat, mendorong partisipasi, pemerkuatan sendi- sendi kehidupan demokratis, dan hukum kurang mendapat perhatian dari para eksponen JIL. Dukungan pada kenaikan harga BBM, minimnya perhatian pada ketidakadilan struktural, gagalnya negara melindungi kaum miskin, adalah eksemplar dari apatisme JIL pada masa depan negara-bangsa sebagai proyek bersama. Sebuah pemikiran, betapapun memesona, hanya dapat bertahan dan meraih konstituensi yang luas karena negasinya atas kenyataan yang timpang dan eksploitatif. Kecanggihan tafsir dalam rangka memperkaya warna-warni hermeneutika Islam mungkin hanya berakhir menjadi kegenitan intelektual, bahkan menanggung nasib daya pukau menara gading. Bukankah iman, rasio, bahkan filsafat, memikul tanggung jawab untuk merespons dan bergerak di dalam realitas obyektif sejarah masyarakatnya, dan bukan sebaliknya. Bila pemikiran keagamaan—termasuk yang diusung oleh JIL selama ini—melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap sejarah yang berlangsung, bukan mustahil radikalisme justru semakin menguat karena dianggap lebih mewakili artikulasi mayoritas yang termarjinalisasikan oleh struktur kekuasaan ekonomi-politik yang menindas. Setiap pemikiran yang diam terhadap pengalaman negatif sejarah masyarakatnya patut dicurigai sebagai ideologi untuk melanggengkan hegemoni kelompok tertentu. Tampaknya adagium "The ruling ideas are the ideas of the ruling class", layak direnungkan. Tanggapan dari eksponen Islam Liberal, Kritik Pungguk Merindukan Bulan Oleh Novriantoni Kahar Aktivis Jaringan Islam Liberal, Menetap di Jakarta Baru berencana merayakan ulang tahun ke-6 pada 22-24 Maret nanti, tanggapan dan kritik soal kiprah Jaringan Islam Liberal atau JIL sudah mulai dibincangkan. Antara lain dalam "Humaniora-Teroka" edisi 17 Februari 2007, Islam Liberal: Kritik atas Kritisisme 'Kenakalan'. Terima kasih kepada Abdul "Dubbun" Hakim, penulisnya, karena sudah halo-halo sejak dini tentang ultah ke-6 JIL. Namun, yang agak membuat miris, walau masih belia, terlalu besar beban (mungkin harapan) yang diinginkan Dubbun dari JIL. Kami berharap dia lupa bahwa JIL, sampai saat ini, bukanlah ormas besar yang punya kuasa dan kemampuan maksimal untuk melakukan misi profetis seperti yang dia idamidamkan. Ketidakcermatan dalam menetapkan neraca antara harapan dan kenyataan itulah yang lantas menghasilkan analisis kurang proporsional tentang JIL. Akan tetapi, baiklah, tulisan ini hanya akan menanggapi beberapa hal yang relevan dari tulisan Dubbun. Pertama, soal jebakan tekstualisme; kedua, soal "kegenitan intelektual"; dan ketiga, soal gejala penyakit 'omdo' (omong doang) di beberapa kalangan yang berharap pada pembaruan Islam. Soal tekstualisme Kekurangpahaman tentang kompleksitas gerakan pembaruan Islam itu tampak dari penilaian Dubbun tentang tekstualisme (kadang dia pakai literalisme) dan bagaimana JIL menanggapinya. Dubbun tidak yakin literalisme dalam beragama sebagai persoalan; sebuah premis yang perlu diperdebatkan di lain tempat. "Literalisme sebagai biang keladi radikalisme dan konservatisme pemikiran juga tak sepenuhnya benar," katanya. Lantas ia bertanya: benarkah ada literalisme dalam pemahaman keagamaan? Karena belajar filsafat bahasa, Dubbun tahu "tidak ada hubungan yang alamiah antara bahasa dan makna, sebagaimana selalu ada jarak antara konsep dan kenyataan". Memang, selalu ada jarak antara apa yang termuat, dikabarkan, dilarang, atau dianjurkan oleh teks-teks agama dengan apa yang ditangkap, terlebih dipraktikkan dalam kehidupan nyata oleh masyarakat paling puritan sekalipun dalam beragama. Karena itu, Yusuf al-Qardlawi, ulama yang ingin moderat dalam mendudukkan hubungan antara teks suci dengan kenyataan, harus membuat dua buku tentang bagaimana umat Islam harusnya berinteraksi dengan teks. Pertama, Kaifa Nata`âmal Ma`al Qur'ân (Bagaimana Kita Bergumul dengan Alquran; kedua, Kaifa Nata`âmal Ma`as Sunnah (Bagaimana Kita Bergumul dengan Sunnah). Namun, dalam kenyataan, bukan tak ada masyarakat jagat raya ini yang tidak terjebak tekstualisme dalam beragama (dan itu bagi saya adalah masalah). Semua dengan derajat yang berbeda-beda. Dalam masyarakat Islam, kuatnya pesona dan kuasa teks itu membuat pemikir seperti Nasr Hamid Abu Zayd pun menjuluki peradaban Islam sebagai "peradaban teks" (hadlâratun nash). Tapi, penyebutan begitu tak berarti bahwa pencapaian peradaban Islam sepenuhnya buah dari tekstualisme yang lupa bagaimana mengelola kenyataan. Ini hanya untuk menunjukkan betapa kuatnya peranan dan posisi teks dalam menuntun dan menginspirasi peradaban Islam, paling tidak secara teoretis. Kesan tekstualisme pada masyarakat Islamseperti dikemukakan Abu Zayd masih sangat terasa pada masyarakat Islam masa kini, dan akan semakin mencolok bila diperbandingkan dengan masyarakat lainnya. Bahkan, untuk masyarakat Indonesia saja, orang Belanda seperti Karel Stenbrink punya kesan bahwa di sini too much religion. Artinya, pengaruh agama, terutama yang tekstualistik, masih sangat dominan terhadap cara berpikir dan bertindak pada masyarakat Indonesia. Lalu bagaimana menanggapi tekstualisme yang akut itu? Haruskah menghindar dari kungkungan teks dalam masyarakat yang konon hanya mengerti bahasa agama? Ini masalahnya! Hampir semua pemikir Islam yang bertanggung jawab, baik di Indonesia maupun di India, masuk ke kancah kontestasi dan perdebatan di level tafsiran tekstual atas agama, walau mereka membaluri tafsiran mereka dengan konteks tertentu. Kemudian muncullah istilah reinterpretasi, rekonstruksi, kontekstualisasi, pribumisasi, desakralisasi, dan lain- lain. Mereka terpaksa atau tepatnya dipaksa oleh situasiuntuk tetap bergumul dengan teks-teks keagamaan, walau mereka tahu bahwa kenyataan sosial juga penting, bahkan teramat penting untuk diabaikan. Dilema itulah yang juga dihadapi JIL saat ini. Juga Paramadina saat masih bergeliat dengan dunia pemikiran, dan banyak gerakan pembaruan Islam lainnya di belahan dunia lain. Gerakan pembaruan Islam yang mengabaikan sama sekali pertarungan di level tekstual, terutama di lingkungan Islam, adalah kenaifan dan menunjukkan bahwa mereka sedang bertarung di medan yang salah. Tapi, menganggap para eksponen gerakan pembaruan itu terjebak tekstualisme saat merespons kenyataan sosial masyarakatnya yang kompleks adalah klaim yang tidak sadar lingkungan. Apakah kita dapat mengatakan bahwa sosok seperti almarhum Nurcholish Madjid atau Cak Nur, yang disanjung sekaligus diabaikan spirit dasar pemikirannya oleh banyak orang dekatnya, adalah seorang tekstualis karena terpaksa bergumul dalam ranah penafsiran-ulang dan penyegaran kembali makna-makna tekstual ajaran Islam? Kegenitan intelektual? Dan, kalau mau jujur, apa yang dihasilkan generasi Cak Nur, terutama dalam pandangan antipembaruan, juga tak sefantastis yang dibayangkan pendukung fanatiknya. Benarlah bahwa Cak Nur berjasa besar menyegarkan dan "menyelamatkan" iman-Islam sebagian masyarakat Islam perkotaan (terutama di Jakarta) lewat Paramadina. Untuk itu saja, dia pantas mendapatkan apresiasi yang tinggi. Namun, apakah hasilnya semaksimal yang dituntutkan Dubbun pada JIL hari ini? Oleh karena itu, kritik yang proporsional dan kredibel terhadap berbagai varian gerakan pembaruan Islam sangat diperlukan. Sejak reformasi bergulir, beberapa buku yang ditulis dengan menggunakan pendekatan kelas sosial misalnya, secara agak serampangan menyebut agama yang diperjuangkan kaum pembaru sebagai Islam borjuis (Cak Nur dan Paramadina), bahkan Islam kolonialis (JIL). Tapi apa yang membuat kritik di atas tampak tidak adil dan kurang kredibel, itu karena mereka tak menempatkan Cak Nur dalam proporsinya sebagai pembaru pemikiran dengan "target pasar" masyarakat menengah-atas perkotaan. Kalau teori tetesan ke bawah berjalan, mereka inilah yang akan menjadi pengecer dan agen pembaruan di masyarakat yang lebih rendah. Mereka lupa bahwa Cak Nur, bahkan gerakan-gerakan pembaruan keagamaan di dunia Islam, bukanlah superhero yang punya daya dukung tinggi. Karena itu, dalam aspek pembaruan Islam, adagium "the ruling ideas are the ideas of the ruling class" tidaklah berlaku. Benar bahwa dalam pemikiran Cak Nur ada ide-ide tentang kerakyatan, keadilan, dan gagasan-gagasan populis lainnya. Tapi, soalnya, apakah dibaca, dipahami dan dicobaterapkan oleh banyak khalayak? Gejala "omdo" Tentu tak salah berharap gerakan pembaruan Islam tak hanya "tampil jadi salah satu varian tafsir atas Islam", tapi hendaknya "berdaya menghadapi realitas material masyarakat yang masih bergulat dengan problem kesenjangan atau kegagalan negara merealisasikan citacita kesejahteraan dan keadilan". Setidaknya, itulah yang dapat dipelajari dari gerakan teologi pembebasan di Amerika Latin. Hanya saja, impian-impian dan harapan mulia itu lebih tepat dibebankan kepada ormas- ormas keagamaan yang lebih tua, sudah mapan, dan punya kapasitas yang memadai. Bila ormas-ormas yang sudah mapan tidak mampu melakukan apa yang mestinya dapat mereka lakukan dengan kapasitas yang mereka punya, maka kritik atasnya adalah sah dan kredibel. Akan tetapi, apakah adil memaksakan organisasi-organisasi seperti JIL dengan tugas-tugas dan peer-peer yang dibebankan Dubbun? Di zaman modern ini, spesialisasi dan rasionalisasi (dua etos penting yang tidak disinggung Dubbun dalam membahas modernisasi yang dianggapnya hasil imposisi dari luar ke dunia Islam) tetap perlu agar kita dapat optimal dalam melakukan tugas masing-masing. Jika tidak, proyek apa pun yang kita lakukan tak akan berbuah dan hanya menjadi impian si pungguk akan bulan. *Tulisan ini pernah dimuat di rubrik ‘ Teroka’, Kompas.