1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah
advertisement
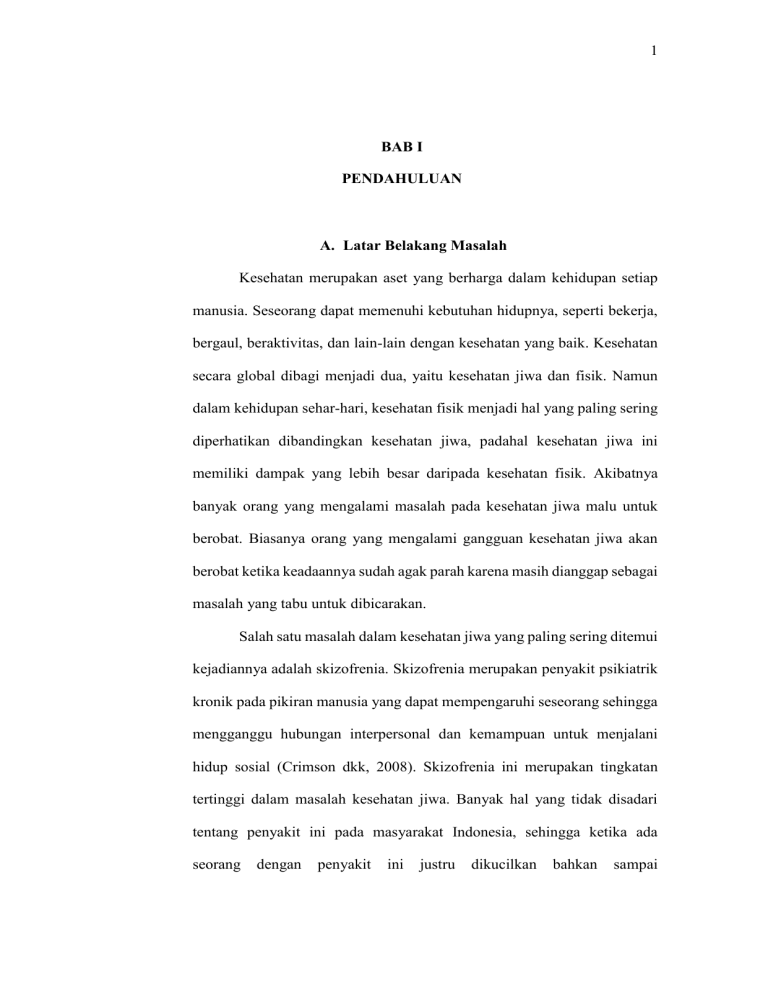
1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Kesehatan merupakan aset yang berharga dalam kehidupan setiap manusia. Seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti bekerja, bergaul, beraktivitas, dan lain-lain dengan kesehatan yang baik. Kesehatan secara global dibagi menjadi dua, yaitu kesehatan jiwa dan fisik. Namun dalam kehidupan sehar-hari, kesehatan fisik menjadi hal yang paling sering diperhatikan dibandingkan kesehatan jiwa, padahal kesehatan jiwa ini memiliki dampak yang lebih besar daripada kesehatan fisik. Akibatnya banyak orang yang mengalami masalah pada kesehatan jiwa malu untuk berobat. Biasanya orang yang mengalami gangguan kesehatan jiwa akan berobat ketika keadaannya sudah agak parah karena masih dianggap sebagai masalah yang tabu untuk dibicarakan. Salah satu masalah dalam kesehatan jiwa yang paling sering ditemui kejadiannya adalah skizofrenia. Skizofrenia merupakan penyakit psikiatrik kronik pada pikiran manusia yang dapat mempengaruhi seseorang sehingga mengganggu hubungan interpersonal dan kemampuan untuk menjalani hidup sosial (Crimson dkk, 2008). Skizofrenia ini merupakan tingkatan tertinggi dalam masalah kesehatan jiwa. Banyak hal yang tidak disadari tentang penyakit ini pada masyarakat Indonesia, sehingga ketika ada seorang dengan penyakit ini justru dikucilkan bahkan sampai 2 dipasung.Prevalensi pasien skizofrenia di dunia adalah sekitar 0,2 – 2% dari total populasi (Ikawati, 2011). Menurut data Riskesdas tahun 2013, di Yogyakarta, prevalensi gangguan jiwa berat yang terjadi adalah sebesar 27% dan ini merupakan prevalensi tertinggi di Indonesia (Riskesdas, 2013) Terapi pada skizofrenia dibagi menjadi dua, yaitu farmakologi dan non farmakologi. Untuk terapi non farmakologi bisa dilakukan dengan memberikan ketrampilan agar meningkatkan fungsi adaptif dari orang yang mempunyai skizofrenia. Terapi farmakologi bisa dilakukan dengan pemberian obat antipsikotik. Selain pengobatan di atas, keluarga dekat juga harus diberikan pengetahuan bagaimana cara menangani orang dengan skizofrenia agar skizofrenianya dapat terkontrol dan orang tersebut dapat kembali bergaul dengan masyarakat. Pada terapi skizofrenia, obat yang digunakan adalah obat antipsikotik yang berefek pada perubahan neurotransmitter dopamin di otak. Obat-obat antipsikotik untuk terapi lini pertama pada pengobatan skizofrenia adalah obat-obat antipsikotik atipikal, seperti risperidon, ziprasidon, aripirazol. Sedangkan obat-obat antipsikotik tipikal digunakan jika terapi dengan obat-obat antipsikotik atipikal tidak menunjukkan hasil yang diharapkan atau kurang cukup memberikan efek terapi yang diinginkan. Obat-obat antipsikotik atipikal dipilih menjadi terapi lini pertama karena pertimbangan risiko efek samping yang ditimbulkan, yaitu gejala ekstrapiramidal. Pada obat antipsikotik atipikal, risiko terjadinya ekstrapiramidal lebih sedikit daripada dengan obat antipsikotik tipikal. 3 Efek samping ekstrapiramidal diduga menjadi salah satu penyebab ketidakpatuhan pasien dalam pengobatan skizofrenia (Wijono dkk., 2013). Akibatnya pasien menjadi sering kambuh dan pengobatan akan menjadi lebih lama bahkan bisa seumur hidup. Untuk mengatasi efek samping ekstrapiramidal yang ditimbulkan, biasanya dokter akan memberikan terapi profilaksis. Pemberian obat yang paling sering diresepkan adalah triheksifenidil atau yang biasa disingkat THP. Ada banyak faktor yang berpengaruh dalam menentukan penggunaan THP, diantaranya usia, jenis kelamin, tipe obat antipsikotik, dan riwayat efek ekstrapiramidal sebelumnya. Penggunaan THP sebagai terapi tambahan pada skizofrenia menurut penelitian Wijono (2013) di Poliklinik Jiwa Dewasa Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo tahun 2010 persentasenya sebesar 44,99%. Studi tentang pola penggunaan THP pada pengobatan skizofrenia belum banyak dilakukan. Penelitian ini digunakan untuk melihat pola penggunaan THP pada pengobatan skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Grhasia. B. Perumusan Masalah 1. Bagaimana gambaran karakteristik pasien skizofrenia yang menerima triheksifenidil di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta tahun 2014? 4 2. Bagaimana pola penggunaan dan peresepan triheksifenidil pada pasien skizofrenia di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta tahun 2014? C. Tujuan Penelitian 1. Mengetahui gambaran karakteristik pasien skizofrenia yang menerima triheksifenidil di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta tahun 2014 2. Mengetahui pola penggunaan dan peresepan triheksifenidil pada pasien skizofrenia di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta tahun 2014 D. Manfaat Penelitian 1. Dapat digunakan sebagai informasi tentang penggunaan triheksifenidil sebagai terapi tambahan untuk gejala ekstrapiramidal pada pasien skizofrenia di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta. 2. Bagi peneliti, menambah wawasan dan pengalaman dalam penelitian. 3. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai studi pendahuluan dan referensi untuk penelitian selanjutnya. E. Tinjauan Pustaka 1. Skizofrenia 5 a. Definisi Skizofrenia Skizofrenia merupakan penyakit psikiatrik yang paling kompleks dan menantang. Skizofrenia menggambarkan sindrom beragam tentang pikiran yang tidak terorganisir dan aneh, delusi, halusinasi, dan fungsi sosial yang terganggu (Crimson dkk., 2008). b. Etiologi Skizofrenia Skizofrenia adalah penyakit kompleks yang tidak memiliki penyebab tunggal. Tidak seperti kebanyakan penyakit kompleks lainnya, skizofrenia tidak diketahui mekanisme patogenetik yang menghubungkan antar faktor risiko terhadap penyakit. Sehingga tidak diketahui secara pasti penyebab skizofrenia (Stefan dkk., 2007). Beberapa teori dikemukakan tentang patogenesis terjadinya skizofrenia. Teori tersebut dikenal dengan hipotesis dopamin, hipotesis neurodevelopmental, hipotesis glutamatergik, hipotesis serotonin, dan genetik 1) Hipotesis dopamin Hipotesis dopamin merupakan hipotesis yang paling awal dan paling banyak diteliti. Dopamin merupakan neurotransmitter di otak. Saat ini telah ditemukan lima macam reseptor dopamine, yaitu reseptor D1, D2, D3, D4, da D5. Kelima reseptor dopamin ini dikelompokkan menjadi dua famili, yakni famili D1 yang terdiri dari reseptor D1 dan D5 serta famili D2 yang meliputi reseptor D2, D3, da 6 D4. Famili D1 pada transduksi sinyalnya berkaitan dengan protein Gs sedangkan famili D2 bekaitan dengan protein Gi. Reseptor dopamin yang lebih berperan pada penyakit skizofrenia adalah reseptor D2 (Ikawati, 2011). Gejala skizofrenia diduga muncul karena neurotransmitter dopaminergik yang berlebihan di mesolimbik otak. Pada hipotesis ini diduga bahwa gejala skizofrenia muncul karena neurotransmiter dopaminergik yang berlebihan di mesolimbic otak. Up-regulation dari reseptor dopamin D2 di caudatus berkaitan dengan risiko terjadinya skizofrenia. Tingginya densitas reseptor dopamine D2 di caudatus dihubungkan dengan kemunduran kognitif pada skizofrenia (Hirvonen dkk., 2005). Hal ini didukung dengan penelitian bahwa ketika seseorang dengan skizofrenia diterapi dengan obat antipsikotik, terdapat penurunan neurotransmisi dopaminergik di otak dan pasien menunjukkan fungsionalitas yang lebih baik pada level perseptual dan gejala positif yang lebih sedikit (El Missiry dkk., 2011). 2) Hipotesis neurodevelopmental Pada hipotesis ini dinyatakan bahwa terdapat kerusakan pada otak di masa-masa dalam kandungan yang mempengaruhi perkembangan otak dan menyebabkan abnormalitas pada saat dewasa. Infeksi ibu hamil selama kehamilannya terutama pada trimester dua atau komplikasi pada perinatal/postnatal juga 7 mempunyai korelasi positif dengan kejadian skizofrenia. Seorang anak yang mengalami infeksi sistem saraf pusat atau kondisi hipoksia selama kelahirannya mempunyai resiko lima kali lebih besar terserang gangguan psikosis termasuk skizofrenia (Dean dkk., 2005). 3) Hipotesis Glutamatergik Sistem glutamatergik merupakan salah satu sistem neurotransmitter yang paling banyak tersebar di otak. Perubahan pada fungsinya, baik hipoaktivitas maupun hiperaktivitas, dapat mengakibatkan toksisitas di otak. Defisiensi glutamatergik menghasilkan gejala yang sama seperti pada hiperaktivitas dopaminergik dan kemungkinan sama seperti skizofrenia (Jones, 2006). 4) Hipotesis Serotonin Pelepasan dopamin berkaitan dengan fungsi serotonin. Penurunan aktivitas serotonin berkaitan dengan peningkatan aktivitas dopamin. Bukti yang mendukung peran potensial serotonin dalam memperantarai efek antipsikotik obat datang dari interaksi anatomi dan fungsional dopamin dan serotonin. Studi anatomi dan elektrofisiologi menunjukkan bahwa saraf serotonergik dari dorsal dan median raphe nuclei terproyeksikan ke badan-badan sel dopaminergik dalam Ventral Tegmental Area (VTA) dan Substansia Nigra (SN) dari otak tengah. Saraf serotonergik dilaporkan berujung 8 langsung pada sel-sel dopaminergik dan memberikan pengaruh penghambatan pada aktivitas dopamin di jalur mesolimbik dan nigrostriatal melalui reseptor 5-HT2A (Ikawati, 2011). 5) Genetik Faktor genetik diduga berpengaruh pada penyakit ini. Risiko skizofrenia pada populasi berkisar antara 0,6 - 1,9%, tetapi risiko menjadi lebih tinggi sebesar pada pasien yang mempunyai riwayat skizofrenia dalam keluarganya. Jika kedua orang tua mempunyai skizofrenia, risiko anaknya akan terkena skizofrenia adalah sebesar 40% (Nieratschker, 2010). Beberapa tahun terakhir telah diteliti tentang polimorfisme gen-gen yang berkontribusi terhadap timbulnya skizofrenia. Beberapa polimorfisme yang diduga meningkatkan risiko penyakit ini adalah COMT (cathecol O methyl transferase) gene, disruptedin-schizophrenia 1 gene (DISC1), DTNBP1 (dystrobrevin binding protein 1) gene, NRG1 SNP1 &2 (neuregulin-1 single nucleotide polymorphism 1&2) gene. Polimorfisme fungsional umum gen COMT yang secara nyata mempengaruhi aktivitas enzim diketahui memengaruhi kognisi dan korteks prefrontal pada manusia. Polimorfisme gen ini diduga sedikit meningkatkan risiko skizofrenia melalui efek pada proses informasi prefrontal yang termediasi dopamin (Fan dkk., 2005). Adanya SNiPs (single nucleotide polymorphism) pada 9 DISC1 berkaitan dengan munculnya skizofrenia dan gangguan skizoafective karena adanya gangguan pada fungsi kognitif (Ishizuka dkk., 2006). Polimorfisme gen DTNBP1 pada p 1635 (terletak pada intron 4), mempengaruhi kejadian skizofrenia. Allel A pada p1635 meningkatkan resiko terjadinya skizofrenia, sementara allel G menurunkan resiko skizofrenia (Galehdari dkk., 2010). Pada polimorfisme gen NRG1 SNP1 mempunyai kecenderungan dengan skizofrenia (Vilella dkk., 2008). c. Gejala Gejala-gejala skizofrenia terentang dari mulai yang ringan hingga yang berat. Pada umumnya, gejala pada skizofrenia dibagi menjadi tiga kelompok,yaitu : gejala positif, gejala negatif, dan gejala kognitif. Gejala positif adalah penyimpangan dari pemikiran dan fungsi yang normal. Gejala-gejala tersebut masuk dalam perilaku “psikotik.” Orangorang dengan gejala ini kadang-kadang tidak mampu untuk membedakan mana yang nyata dan yang tidak.Gejala negatif mengacu kepada kesulitan untuk mengeskpresikan emosi dan berfungsi secara normal. Saat seseorang dengan skizofrenia mengalami gejala negatif, gejalanya mirip depresi. Gejala kognitif tidak mudah untuk dilihat, akan tetapi hal ini dapat mempersulit orang tersebut untuk mendapatkan pekerjaan atau merawat dirinya sendiri (Anonim, 2009). 10 Tabel I. Gejala Skizofrenia (Crimson dkk., 2008) Gejala Positif Gejala Negatif Gejala Kognitif Curiga Delusi Perasaan tumpul Alogia Gangguan perhatian Halusinasi Bicara tidak teratur Anhedonia` Avoilition menjadi Gangguan ingatan Gangguan fungsi melakukan sesuatu d. Klasifikasi Skizofrenia dapat dibedakan menjadi beberapa tipe menurut PPDGJ III tahun1993, yaitu : 1) Skizofrenia paranoid (F 20.0) Skizofrenia tipe paranoid merupakan tipe skizofrenia yang paling sering ditemukan. a) Memenuhi kriteria skizofrenia b) Halusinasi dan/ waham harus menonjol : halusinasi auditori yang memberi perintah atau auditorik yang berbentuk tidak verbal; halusinasi pembauan atau pengecapan rasa bersifat seksual; waham dikendalikan, dipengaruhi, pasif atau keyakinan dikejar-kejar c) Gangguan afektif, dorongan kehendak, dan pembicaraan serta gejala katatonik relatif tidak ada. 2) Skizofrenia hebefrenik (F 20.1) a) Memenuhi kriteria skizofrenia b) Pada usia remaja dan dewasa muda (15 – 25 tahun) 11 c) Kepribadian premorbid : pemalu, senang menyendiri d) Gejala bertahan 2 – 3 minggu e) Gangguan afektif dan dorongan kehendak, serta gangguan proses pikir umumnya menonjol. Perilaku tanpa tujuan dan tanpa maksud. Preokupasi dangkal dan dibuat-buat terhadap agama, filsafat, dan tema abstrak. f) Perilaku yang tidak bertanggung jawab dan tidak dapat diramalkan, mannerism, cenderung senang menyendiri, perilaku hampa tanpa tujuan, dan hampa perasaan g) Afek dangkal dan tidak wajar, cekikikan, puas diri, senyum sendiri, atau sikap tinggi hati, tertawa menyeringai, mengibuli secara bersenda gurau, keluhan hipokondriakal, ungkapan kata diulang-ulang h) Proses pikir disorganisasi, pembicaraan tak menentu, inkoheren. 3) Skizofrenia katatonik (F 20.2) a) Memenuhi kriteria diagnosis skizofrenia b) Stupor (amt berkurang reaktivitas terhadap lingkungan, gerakan, atau aktivitas spontan) atau mutisme c) Gaduh-gelisah (tampak aktivitas motoric tak bertujuan tanpa stimuli eksternal) d) Menampilkan posisi tubuh tertentu yang aneh dan tidak wajar serta mempertahankan posisi tersebut 12 e) Negativisme (perlawanan terhadap perintah atau melakukan ke arah yang berlawanan dari perintah) f) Rigiditas (kaku) g) Fleksibilitas cerea (waxy flexibility) yaitu mempertahankan posisi tubuh dalam posisi yang dapat dibentuk dari luar h) Command automatism (patuh otomatis dari perintah) dan pengulangan kata-kata serta kalimat i) Diagnosis katatonik dapat tertunda jika diagnosis skizofrenia belum tegak karena pasien yang tidak komunikatif. 4) Skizofrenia tak terinci atau undifferentiated (F 20.3) a) Memenuhi kriteria umum diagnosis skizofrenia b) Tidak paranoid, hebefrenik, katatonik c) Tidak memenuhi skizofrenia residual atau depresi pascaskizofrenia. 5) Skizofrenia pasca-skizofrenia (F 20.4) a) Memenuhi kriteria umum diagnosis skizofrenia selama 12 bulan terakhir ini b) Beberapa gejala skizofrenia masih tetap ada (tetapi tidak lagi mendominasi gambaran klinisnya) c) Gejala-gejala depresih menonjol dan mengganggu, memenuhi paling sedikit kriteria untuk episode depresif (F 32.-) dan telah ada dalam kurun waktu paling sedikit dua minggu. 13 Apabila pasien tidak menunjukkan lagi gejala skizofrenia, diagnosis menjadi episode depresif (F 32.-). Bila gejala skizofrenia masih jelas dan menonjol, diagnosis harus tetap salah satu dari subtype skizofrenia yang sesuai (F 20.0 – F 20.3). 6) Skizofrenia residual (F 20.5) a) Gejala negatif dari skizofrenia yang menonjol, misalnya perlambatan psikomotorik, aktivitas yang menurun, afek yang menumpul, sikap pasif dan ketiadaan inisiatif, kemiskinan dalam kuantitas atau isi pembicaraan, komunikasi non verbal yang buruk seperti dalam ekspresi muka, kontak mata, modulasi suara dan posisi tubuh, perawatan diri dan kinerja sosial yang buruk b) Sedikitnya ada riwayat satu episode psikotik yang jelas dimasa lampau yang memenuhi kriteria untuk diagnosis skizofrenia c) Sedikitnya sudah melewati kurun waktu satu tahun dimana intensitas dan frekuensi gejala yang nyata seperti waham dan halusinasi yang telah sangat berkurang (minimal) dan telah timbuk sindrom negatif dari skizofrenia d) Tidak terdapat dementia atau penyakit/gangguan otak organic lain, depresi kronis atau isntitusionalisasi menjelaskan disabilitas negatif tersebut. 7) Skizofrenia simpleks (F 20.6) yang dapat 14 a) Diagnosis skizofrenia simpleks sulit dibuat secara meyakinkan karena tergantung pada pemantapan perkembangan yang berjalan dan progesif dari : (1) Gejala negatif yang khas dari skizofrenia residual tanpa didahului riwayat halusinasi, waham, atau manifestasi lain dari episode psikotik (2) Disertai dengan perubahan-perubahan perilaku pribadi yang bermakna, bermanifestasi sebagai kehilangan minat yang mencolok, tidak berbuat sesuatu, tanpa tujuan hidup, dan penarikan diri secara social. b) Gangguan ini kurang jelas gejala psikotiknya dibandingkan subtipe skizofrenia lainnya. 8) Skizofrenia lainnya (F 20.8) Termasuk skizofrenia chenesthopathic (terdapat suatu perasaan yang tidak nyaman, tidak enak, tidak sehat pada bagian tubuh tertentu), gangguan skizofeniform YTI. 9) Skizofrenia tak spesifik (F 20.7) Merupakan tipe skizofrenia yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam tipe yang telah disebutkan. 2. Terapi Skizofrenia Menurut National Institute of Mental Health (2009), Pengobatan pada skizofrenia didasarkan untuk mengurangi gejala yang muncul karena 15 penyebab pastinya belum diketahui. Pengobatan meliputi terapi dengan obatdan terapi psikososial. a. Terapi psikososial. Terapi ini dapat membantu setelah pasien menemukan obat yang cocok dan obat itu bekerja secara baik. Terapi psikososial umumnya lebih efektif diberikan pada saat pasien berada dalam fase perbaikan dibandingkan pada fase akut. Terapi ini membantu pasien skizofrenia dalam menghadapi permasalahan yang ada seharihari, seperti susahnya berkomunikasi, bekerja, merawat diri, membentuk dan mempertahankan hubungan. Terapi ini meliputi: 1) Pemberhentian dari narkotik dan alkohol. Penyalahgunaan narkoba dan alkohol terkadang sering dijumpai pada pasien skizofrenia 2) Edukasi keluarga. Biasanya setelah pasien skizofrenia menjalani rawat inap, akan dikembalikan lagi ke keluarganya. Untuk itu perlu adanya edukasi bagi keluarga tentang skizofrenia. Hal ini akan membantu dalam pencapaian target terapi untuk pasien dan juga sarana agar pasien skizofrenia semakin patuh minum obat. Keterampilan pengelolaan penyakit. Dengan adanya ketrampilan pengelola penyakit, diharapkan nantinya pasien akan lebih mengerti tentang penyakitnya dan dapat mencegah kekambuhan. 3) Rehabilitasi. Membantu mendapatkan pekerjaan dan keterampilan untuk menjalani kehidupan sehari-hari 16 4) Self-help groups. Sesama pasien atau keluarga saling ditemukan untuk berbagi pengalaman dan juga agar pasien tidak merasa sendiri. 5) Terapi kognitif dan perilaku. Terapi ini menolong pasien yang gejalanya tidak dapat dikendalikan dengan obat antipsikotik. Terapi ini dapat mengurangi gejala dan mencegah kekambuhan. b. Obat antipsikotik Obat antipsikotik mulai tersedia sejak pertengahan 1950. Tipe awal yang pertama muncul adalah obat antipsikotik konvensional atau tipikal. Beberapa contoh obat antipsikotik tipikal yang banyak digunakan adalah haloperidol, klorpromazin, flufenazin, ferfenazin. Obat-obat antipsikotik tipikal bekerja memblok reseptor dopamin, khususnya reseptor D2. Pengeblokan pada reseptor D2 di mesolimbik dapat mengurangi gejala positif pada skizofrenia. Obat antipsikotik atipikal atau generasi kedua secara farmakologi mekanisme aksinya berbeda daripada antipsikotik sebelumnya terutama dalam hal menurunkan aktivitas dopamin. Obat antipsikotik atipikal lebih mempunya aktivitas dalam menurunkan neurotransmitter lain, yaitu serotonin dan norepinefrin. (Miyamoto dkk., 2005). Contoh obat yang termasuk ke dalam golongan obat antipsikotik atipikal adalah olanzapine, risperidon, clozapine, quetiapine, dan ziprasidon. Obat antipsikotik atipikal merupakan lini pertama dalam pengobatan skizofrenia karena efek samping yang ditimbulkan cenderung lebih kecil. 17 Gambar 1 merupakan algoritma terapi skizofrenia. Terapi antipsikotik yang digunakan sebagai lini pertama adalah antipsikotik atipikal. Antipsikotik tipikal dapat digunakan dalam terapi jika antipsikotik atipikal memberikan respon parsial atau sama sekali tidak memberikan respon. Tahap 1. Episode psikosis yang pertama Atipsikotik Tunggal Lebih disaraan antipsikotik golongan kedua Respon parsial atau tanpa respon Tahap 2. Antipsikotik generasi pertama ataupun generasi kedua tunggal selain yang telah digunakan pada tahap 1 Respon parsial atau tanpa respon Tahap 3. Klozapin Respon parsial atau tanpa respon Tahap 4. Klozapin + antipsikotik lain atau terapi elektrokonvulsif. Tanpa respon Tahap 5 . Antipsikotik tunggal selain yang telah digunakan pada tahap 1 dan 2 Tahap 6 . Terapi kombinasi Gambar 1. Algoritma Terapi Skizofrenia (Crimson dkk., 2008) 18 3. Efek Samping Antipsikotik Meskipun antipsikotik tergolong efektif untuk terapi skizofrenia, tetapi mempunyai efek samping yang serius seperti ekstrapiramidal, penambahan berat badan, efek metabolik, kenaikan prolaktin, dan perpanjangan interval QTc. a. Ekstrapiramidal (EPS) Banyak antipsikotik tipikal mempunyai efek antikolinergik yang minimal sehingga mempunyai kecenderungan menimbulkan efek samping ekstrapiramidal. Sedangkan untuk antipsikotik atipikal, efek antikolinergiknya bervariasi tapi cenderung lebih rendah efeknya dalam menimbulkan efek samping ekstrapiramidal daripada antipsikotik tipikal (Pakpoor, 2014). b. Penambahan berat badan dan efek metabolik Salah satu efek samping dari penggunaan obat antipsikotik atipikal adalah penambahan berat badan dan sindrom metabolik. Pasien yang menerima obat antipsikotik harus secara berkala diukur Body Mass Index (BMI) dan lingkar pinggang. Antipsikotik atipikal cenderung meningkatkan kolestrol dan trigliserida dan kenaikan dari trigliserida berhubungan dengan obesitas dan diabetes (Pakpoor, 2014). c. Kenaikan prolaktin Salah satu konsekuensi dari penggunaan antipsikotik yang tidak selektif adalah pemblokan reseptor D2 pada laktotrof dan akan mengakibatkan kenaikan prolaktin. Kenaikan prolaktin dalam waktu 19 yang lama akan menyebabkan hiperprolaktinemia dan dapat menyebabkan ginekomastia, galaktorea, menstruasi yang tidak teratur, disfungsi seksual, demineralisasi tulang (osteoporosis) (Pakpoor, 2014). d. Perpanjangan Interval QTc Obat-obat antipsikotik dapat mempengaruhi ECG dan dianggap berbuhungan dengan aritmia ventrikuler dan kematian jantung mendadak (Pakpoor, 2014). 4. Efek Samping Ekstrapiramidal Efek samping ekstrapiramidal atau yang biasa disebut gejala ekstrapiramidal merupakan kelainan yang berhubungan dengan pergerakan diinduksi oleh obat antipsikotik atau obat yang memblok dopamine (Courey, 2007). Gejala ekstrapiramidal merupakan efek samping yang pertama kali muncul setelah obat antipsikotik golongan pertama atau tipikal digunakan. Gejala ekstrapiramidal yang diinduksi oleh antipiskotik terbagi menjadi sindrom akut dan tardif. Gejala ekstrapiramidal sindrom akut terjadi dalam hitungan jam atau minggu setelah inisiasi atau penambahan dosis antipsikotik dan termasuk di dalamnya adalah distonia, akathisia, dan parkinsonisme. Diskinesia tardif merupakan gejala ekstrapiramidal dengan onset telambat dan biasanya terjadi setelah penggunaan antipiskotik jangka panjang (Jesic dkk., 2012). Antagonisme reseptor dopamine D2 dipercaya berperan tidak hanya pada efek antipsikotik, tetapi juga menyebabkan gejala esktrapiramidal. 20 Sebanyak 75 – 80% pengeblokan reseptor dopamine D2 dapat menyebabkan timbulnya gejala ekstrapiramidal akut. Gejala ekstrapiramidal muncul pada kurang lebih 90% pasien skizofrenia yang menggunakan antipsikotik tipikal, seperti pada haloperidol (Jesic dkk., 2012). a. Distonia Merupakan keadaan otot yang tidak normal atau sering disebut dengan kejang otot. Istilah yang lebih akurat adalah kontraksi otot yang diperpanjang dengan onset yang cepat biasanya 24 – 96 jam setelah pemberian atau peningkatan dosis. Distonia ini merupakan salah satu penyebab pasien menjadi tidak patuh dalam pengobatan. Distonia yang diinduksi antipsikotik biasanya terjadi di sekitar tangan, meskipun terkadang terjadi di beberapa otot. Tanda-tanda yang tampak seperti kekakuan rahang, tonjolan lidah, kejang faring, disfagia, dan terkadang sulit bernafas (Jesic dkk., 2012). Faktor risiko distonia diantaranya adalah penggunaan jenis dan dosis tinggi antipsikotik, usia muda, laki-laki, retardasi mental, adanya riwayat distonia, dan penyalahgunaan alkohol. Distonia terkadang bisa disebabkan karena antiemetik dan beberapa antidepresan. Semua antipsikotik, tak terkecuali antipsikotik atipikal, dapat memicu distonia. Durasi distonia dapat diperpanjang ketika digunakan antipsikotik dalam bentuk depot (Jesic dkk., 2012). 21 Patogenesis distonia masih belum ditemukan, meskipun berhubungan dengan hipersensitivitas sekunder dari penghambatan reseptor D2. Ada kemungkinan untuk remisi tiba-tiba, tetapi dalam banyak kasus, distonia berlanjut hingga bertahun-tahun dan sangat melelahkan serta mendapatkan stigma buruk (Jesic dkk., 2012). Untuk mengatasi distonia dapat digunakan antikolinergik intravena atau intramuskular atau benzodiazepin sebagai terapi pilihan. Terapi profilaksis untuk distonia tidak direkomendasikan dalam penggunakan obat antipsikotik tipikal secara rutin, tetapi dapat digunakan pada antipsikotik tipikal yang mempunyai potensi tinggi (haloperidol, klorpromazin). Distonia dapat diminimalisasi dengan penggunaan antispikotik dosis rendah. Obat antipsikotik atipikal mempunyai efek yang lebih rendah dalam menimbulkan distonia (Crimson dkk., 2008). b. Akathisia Akathisia merupakan efek samping antipsikotik yang serius dan paling banyak terjadi. Akathisia dianggap sebagai gangguan gerakan yang diinduksi penghambatan reseptor dopamin oleh neuroleptik dan antiemetilk. Gangguan ini juga dapat disebabkan oleh agen serotonergik, inhibitor reuptake serotonin, dan kokain (Jesic dkk., 2012). Sindrom ini terdiri dari komponen subjektif dan objektif. Tandatanda akathisia pada pasien seperti adanya perasaan gelisah dan dorongan tak tertahankan untuk bergerak. Kegelisahan khususnya 22 ditandai dengan gerakan seluruh tubuh, tapi terkadang hanya terjadi pada kaki dengan bentuk mioklonus kaki. Pasien akan melakukan gerakan menyilangkan kaki, duduk tidak tenang di kursi atau tempat tidur, melompat, berdiri, dan secepatnya kembali pada posisi sebelumnya. Berdasarkan onset yang berhubungan dengan inisiasi atau penambahan antipsikotik, akathisia dapat dibagi menjadi akut, tardif, kronik, dan penarikan yang berhubungan dengan penhentian antipsikotik. Akut terjadi segera setelah inisiasi atau penambahan dosis antipsikotik dalam kurun waktu dua minggu dan tardif terjadi paling tidak tiga bulan setelah terapi, tanpa memperhatikan perubahan dalam antipsikotik. Kronik terjadi setelah lebih dari tiga bulan. Bentuk-bentuk yang telah disebutkan di atas tidak berbeda signifikan dengan akathisia akut pada gejala motorik (Jesic dkk., 2012). Prevalensi bervariasi dari 5 – 36,8%. Data dari CATIE menunjukkan akathisia terjadi pada 10 – 20% pasien yang menerima antipsikotik atipikal, sedangkan pada pasien yang menerima antipsikotik tipikal prevalensi berkisar antara 20 – 52%. Belum ada studi tentang akathisia terkait usia dan jenis kelamin. Terdapat hubungan antara penggunaan antipsikotik reseptor D2 dengan dosis (Jesic dkk., 2012). Saat ini, terdapat dua manajemen terapi untuk mengurangi akathisia, yaitu modifikasi regimen obat antipsikotik dan/atau penggunaan obat anti-akathisia. Terapi yang digunakan pada akathisia saat ini adalah β- 23 blocker, benzodiazipn, antikolinergik, dan antagonis reseptor serotonin (Crimson dkk., 2008). c. Pseudoparkinsonisme Parkinson yang diinduksi oleh antipsikotik merupakan bentuk parkinson kedua yang paling banyak diderita oleh pasien berusia lanjut selain idiopatik parkinson. Interval antara pemberian antipsikotik dan onset parkinsonisme bervariasi mulai dari hitungan hari hingga beberapa bulan. Tidak seperti penyakit parkinson, gejala biasanya bilateral dan simetrikal. Terdapat tiga gejala, yaitu bradikinesia, kekakuan otot, dan tremor. Pada pasien yang sudah menerima antipsikotik, prevalensinya adalah 15% meskipun terdapat kesulitan untuk menentukan secara tepat karena studi epidemiologi menggolongkannya sebagai bentuk parkinsonisme atau gangguan gerakan yang diinduksi obat secara umum (Thanvi dan Treadwell, 2009). Faktor risiko diantaranya adalah usia, jenis kelamin perempuan, tipe obat yang digunakan, dosis dan durasi terapi, defisit kognitif, dan onset awal gejala ekstrapiramidal (Thanvi dan Treadwell, 2009). Mekanisme patofisiologi berhubungan dengan penghambatan reseptor dopamine D2 dan serotonin 5-HT2A dan affinitas rendah dari antipsikotik tertentu ke reseptor asetilkolin (Jesic dkk., 2012). Untuk mengatasi gejala ini, dapat diberikan obat antikolinergik, seperti triheksifenidil, benztropin, difenhidramin, biperiden. Terapi 24 profilaksis pada gejala ini sebenarnya tidak terlalu direkomendasikan, sama seperti gejala distonia, terutama untuk obat antipsikotik golongan kedua atau atipikal. Terapi jangka panjang juga masih kontroversial, untuk pasien yang gejala parkinsonisme sudah menghilang dapat tidak digunakan antikolinergik setelah 6 minggu sampai 3 bulan (Crimson dkk., 2008). d. Diskinesia Tardif Diskinesia tardif ditunjukkan dengan adanya pergerakan choreoathetoid bagian wajah, kaki dan tangan, bagasi, dan otot pernafasan. Gerakan ditandai dengan adanya kegembiraan yang menghilang selama tidur. Beberapa pasien tidak sadar dengan adanya gerakan yang tidak disadari (Haddad dan Dursum, 2008). Gejala ini dapat dialami oleh semua pasien yang mendapat antipsikotik. Gejala ini mulai nampak setelah penggunaan antipsikotik berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Kondisi ini dapat tetap parah ketika antipsikotik dihentikan atau bahan ireversibel (Jesic dkk., 2012). Prevalensi terjadinya diskinesia tardif sebesar 5% pada pasien dewasa yang menerima antipsikotik dan secara kumulatif 25 – 30% pada pasien dewasa. Kejadian cenderung lebih rendah pada penggunaan antipsikotik atipikal. Gejala ini lebih jarang dialami pada pasien yang menggunakan antipsikotik atipikal berupa klozapin. Insiden tardif diskinesia bervariasi tergantung pada tipe dan dosis antipsikotik, lama penggunaan, jenis kelamin, umur pasien, meskipun terdapat pendapat 25 yang mengatakan bahwa pasien akan menderita gejala ini jika diberikan antipsikotik dalam waktu yang lama. Pasien usia lanjut dan pasien wanita mempunyai faktor risika yang lebih besar. Faktor risiko juga termasuk kerusakan otak, demensia, gangguan mood, durasi terapi antipsikotik, penggunaan terapi antikolinergik antiparkinson, dan kejadian gejala ekstrapiramidal sebelumnya. Diskinesia tardif secara patofisiologi terjadi karena sensitivitas yang diinduksi oleh neuroleptik tergantung dosis pada reseptor D2 di jalur nigrostriatal (Jesic dkk., 2012). Saat terjadi diskinesia tardif, pasien dianjurkan untuk menghentikan obat antipsikotik. Namun banyak pasien yang membutuhkan antipsikotik sebagai terapi. Pada kasus tersebut, dosis antipsikotik diturunkan paling minimum atau diganti dengan antipsikotik yang mempunyai kecenderungan menimbulkan tardif diskinesia terendah, seperti clozapine atau quetiapin. Penggunaan vitamin E, asam valproat, asam lemak esensial, dan benzodiazepin juga dapat dipertimbangkan, tetapi hasilnya tidak terlalu meyakinkan (Haddad dan Dursum, 2008). e. Algoritma Terapi Gejala Ekstrapiramidal Gambar 2 menunjukkan algoritma penatalaksanaan gejala esktrapiramidal. Terapi gejala ekstrapiramidal secara profilaksis dilakukan jika sudah dilakukan penilaian terhadap kondisi pasien. Tiga hal yang perlu dilakukan sebelum memulai memutuskan untuk memberikan terapi gejala ekstrapiramidal adalah mengetahui riwayat 26 gejala ekstrapiramidal sebelumnya, adanya kemungkinan untuk terjadi gejala ekstrapiramidal jika dilihat dari jenis terapinya, dan adanya sisa gejala ekstrapiramidal jika sebelumnya sudah terjadi gejala ekstrapiramidal. Distonia dapat diterapi dengan pemberian antihistamin (difenhidramin) secara intramuskular atau antikolinergik (sulfa atropine) secara parenteral (intramuscular). Selain itu juga dapat diberikan diazepam injeksi. Obat antikolinergik dapat menghambat asetilkolin yang dapat memberikan perasaan tenang kepada pasien. Pada saat kejadian akut, difenhidramin dapat diberkan, meskipun antihistamin tetapi yang digunakan adalah peran antikolinergiknya. Antikolinergik yang sering digunakan adalah triheksifenidil. Triheksifenidil merupakan antagonis reseptor asetilkolin muskarinik. Dosis triheksifenidil saat awal digunakan adalah 1 mg/hari dan ditingkatkan 1 mg setiap 3 – 5 hari dalam periode satu bulan hingga tercapai 6 mg/hari (Cloud dan Jinnah, 2010). Strategi pertama dalam penanganan parkinsonisme yang diinduksi antipsikotik adalah penurunan dosis antipsikotik yang digunakan. Namun banyak didapati pasien yang penyakitnya justru menjadi semakin parah ketika dosis antipsikotik diturunkan, sehingga penambahan obat untuk mengatasi gejala ekstrapiramidal menjadi alternatif selanjutnya. Parkinsonisme ini dapat diterapi dengan antihistamin (difenhidramin) dan antikolinergik (triheksifenidil). 27 Seperti pada distonia, dosis triheksifenidil pada saat awal digunakan adalah 1 mg/hari dan dapat ditingkatkan hingga 6 mg/hari. Akathisia merupakan gejala ekstrapiramidal yang sulit diterapi. Sebagaimana parkinsonisme, strategi pertama adalah penurunan dosis antipsikotik, tetapi cara ini bukanlah yang paling efektif. Strategi berikutnya adalah penambahan obat untuk mengurangi akatisia, dengan cara pemberian β-blocker merupakan yang paling efektif. Propranolol dosis 30 – 120 mg/hari dalam dosis terbagi merupakan terapi yang direkomendasikan. Strategi selanjutnya jika tidak berhasil adalah dengan golongan benzodiazepine, tetapi perlu diperhatikan pada adanya penyalahgunaan dari obat ini. Alternatif terakhir adalah dengan mengganti antipsikotik. Aspek utama pada pengendalian diskinesia tardif adalah penghentian atau penggantian antipsikotik, tetapi dengan penurunan dosis terlebih dahulu. Antipsikotik diganti dengan atipikal generasi baru seperti quetiapin dan klozapin. Namun obat-obat tersebut tidak bagus jika digunakan untuk pengobatan tardif diskinesia jangka panjang. Kemungkinan besar antipsikotik atipikal dapat menghambat reseptor D2 dan menyebabkan tardif diskinesia (Waln dan Jankovic, 2013). Evaluasi perlu dilakukan pada pengobatan gejala ekstrapiramidal. Evaluasi dilakukan dua minggu setelah penggunaan pada terapi profilaktik. Obat dapat diturunkan dosisnya jika sudah tidak tampak adanya gejala ekstrapiramidal. 28 1. Anamnesis : riwayat penggunaan antipsikotik, dosis, dan lamanya 2. Riwayat kondisi medis umum 3. Pemeriksaan fisik dan gejala sindrom ekstrapiramidal (instrumen Skala Penilaian Gejala Ekstrapiramidal/SPGE) 4. Pemeriksaan Penunjang : Lab, dll Riwayat EPS sebelumnya Predisposisi terjadinya EPS Gejala sisa EPS Pemberian anti EPS atau THP profilaktik Distonia Parkinsonisme Difenhdramin 2 ml im atau Inj benzodiazepin (diazepam 10 mg im) atau sulfas atropine 1-2 ml ampul im Triheksifeni dil 1-3 x 2 mg/hari Antipsikotik saja Terjadi EPS Turunkan dosis antipsikotik Difenhidra min 25 -100 mg/hari atau THP 1-3 x 2mg/hari Ganti antipsikotik Akatisia Diskinesia Tardif Turunkan dosis antipsikotik Beta bloker : propranolol 3x10-40 mg/hari per oral atau klonidin 3x0,1 mg/hari/oral Diazepam inj/ lorazepam oral Ganti antipsikotropika. Diskinesia tardif ringan Olanzapine/quetiia pin Diskenisa tardif berat klozapin Ganti antipsikotik 1. Lanjutkan pengobatan gejala EPS 2. Turunkan/stop gejala EPS jika selama 14 hari tidak ada gejala 1. Pengobatan EPS 2. Observasi 3 bulan EPS muncul kembali Tidak ada EPS Antipsikotik saja Gambar 2. Algoritma Penatalaksanaan Gejala Ekstrapiramidal (EPS) di Poliklinik Jiwa Dewasa RSCM (RSCM, 2007) 29 5. Triheksifenidil a. Struktur molekul Gambar 3. Struktur Molekul Triheksifenidil b. Mekanisme aksi Mekanisme aksi triheksifenidil dalam mengatasi masalah ekstrapiramidal adalah dengan pengeblokan aktivitas intrakolinergik striatal, yang mana relatif meningkat daripada aktivitas dopaminergik nigrostriatal yang menurun karena pengeblokan oleh antipsikotik. Pengeblokan aktivitas kolinergik mengubah kembali ke keadaan semula. c. Efek samping Efek samping triheksifenidil dibagi menjadi dua, yaitu perifer dan pusat. Efek samping perifer terjadi karena adanya pengeblokan pada parasimpatetik muskarinik. Antikolinergik mengurangi produksi saliva, keringat, dan sekresi bronkial. Selain itu, antikolinergik juga berpengaruh pada mata dan jantung. Dilatasi pada pupil dapat menyebabkan fotofobia dan pandangan kabur. Pada jantung dapat menyebabkan kenaikan denyut jantung. Pada pusat, gangguan ingatan merupakan efek samping yang paling sering dijumpai karena ingatan sangat tergantung dari aktivitas kolinergik. 30 d. Interaksi obat Efek antikolinergik akan meningkat, termasuk efek sampingnya jika digunakan bersama dengan amantadine. e. Penggunaan klinik Triheksifenidil telah disetujui oleh Food and Drug Administration (FDA) untuk pengobatan segala bentuk parkinsonisme. Dosis untuk parkinsonisme biasanya adalah 5 – 30 mg. Dosis yang lebih tinggi (sampai 75 mg/hari) digunakan untuk mengatasi distonia (Schartzberg dkk., 2009). F. Keterangan Empiris Penggunaan triheksifenidil pada pasien skizofrenia mampu mengatasi permasalahan efek samping berupa gejala ekstrapiramidal. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pola pengobatan triheksifenidil pada pasien skizofrenia di Instalasi Rawat Inap Rumah Ssakit Jiwa Grhasia Yogyakarta.