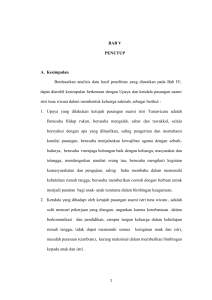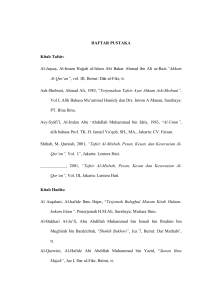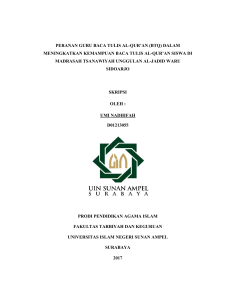Jurnal Bimas Islam Vol. 9 No. 2 Tahun 2016
advertisement

Daftar Isi Pemikiran Fikih Maliki Tentang Pernikahan dan Implementasinya dalam UU Perkawinan Aljazair Maliki Fiqh Thinking about Marriage and Its Implementation in Algeria Marriage Law — 211 Engkos Kosasih Administrasi Perkawinan di Dunia Islam Modern Administration Marriage in the Modern Islamic World — 259 Ahmad Tholabi Kharlie Implementasi Maqâshid Al-Syarî’ah dalam Putusan Bahts Al-Masâ’il tentang Perkawinan Beda Agama Implementation of Maqâshid Al-Syarî’ah in Decision of Bahts AlMasâ’il on Interfaith Marriage — 293 Ali Mutakin Konsep ‘darajah’ : Solusi Al-Quran dalam Mengatasi Beban Ganda Wanita Karier The concept of ‘darajah’: Quranic Solution In Overcome Dual Load of Career Women — 323 Muhammad Amin Pengaruh Agama Islam Terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia The influence of Islamic Religion againstthe Legal Developments in Indonesia — 341 Fabian Fadhly Prinsip-prinsip Keadilan Wanita dalam Islam: Sebuah Kajian Pra-nikah Principles of Justice Women in Islam: A Study of Pre-marriage — 371 Ru’fah Abdullah Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 Pemikiran Fikih Maliki Tentang Pernikahan dan Implementasinya dalam UU Perkawinan Aljazair _211 Maliki Fiqh Thinking about Marriage and Its Implementation in Algeria Marriage Law Pemikiran Fikih Maliki Tentang Pernikahan dan Implementasinya dalam UU Perkawinan Aljazair Engkos Kosasih Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung Email:[email protected] Abstract : Family law in Islamic countries worth to be observe as an academic study materials. Birth of taqnin efforts in the problem of ahwal as-sakhsiyyah is very beneficial for tajdid or renewal of Islamic law. Maliki madhhab have unique and specific istinbath method that allows for variation of ijtihad which makes varied as well. The writer concludes that power influence maliki madhhab in the Algerian family law is clearly appear. Articles in family law adopted by Maliki madhhab even though it keeps accommodating another madhhab thought. The domination of Maliki madhhab does not interfere the existence of other articles which are diametrically Maliki madhhab itself. This theory Malikiyyah law implementation is textual, but the codification law in practice tends to be contextualist. Abstraksi : Hukum keluarga di negara-negara Islam layak untuk dicermati sebagai bahan kajian akademis. Kelahiran upaya taqnin dalam masalah ahwâl as-sakhsiyyah ini sangat bermanfaat bagi tajdîd atau pembaharuan hokum islam. Madzhab maliki memiliki keunikan dan kekhususan metode istinbath yang memungkinkan adanya variasi hasil ijtihad yang bervariatif pula. Penulis berkesimpulan bahwa daya pengaruh madzhab maliki dalam hokum keluarga Aljazair itu sangat nampak. Pasal-pasal dalam hokum keluarga banyak mengadopsi pemikiran madzhab maliki walaupun tetap mengakomodasi madzhab lainnya. Dominasi maliki tidak menghalangi adanya pasal-pasal lain yang justru bersikap diametral dengan madzhab maliki itu sendiri. Teori implementasi hokum malikiyyah ini bersifat tekstualis, namun kodifikasi hukum dalam prakteknya cenderung bersifat kontekstualis. Keywords: Family Law, Madhhab, Marriage 212_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 A.Pendahuluan Salah satu ajaran yang penting dalam Islam adalah pernikahan. Begitu pentingnya ajaran tentang pernikahan tersebut sehingga dalam al-Qur’an terdapat sejumlah ayat baik secara langsung maupun tidak langsung berbicara mengenai masalah pernikahan dimaksud.1Perkawinan atau pernikahan dalam istilah ilmu fiqh klasik berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadz inkah atau tazwîj. Akan tetapi menurut penulis definisi tersebut sangat kaku dan sempit, sebab nikah hanya sebagai perjanjian legalisasi hubungan seksual antara pria dan wanita saja. Seolah-olah hakikat pernikahan hanya pelampiasan nafsu dan syahwat saja. Dalam kaitannya untuk menghilangkan pandangan masyarakat tentang arti nikah, sekaligus menempatkan pernikahan sebagai sesuatu yang mempunyai kedudukan mulia, ulamamuta’akhirîn berupaya menjelaskan dan meluaskan arti nikah, dengan memberikan gambaran yang komprehensif dengan definisinya,yaitu “Nikah ialah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dan perempuan dan saling tolong-menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya.” 2 Pernikahan memiliki fungsi adiluhung baik dari aspek teologis, psikologis, biologis, maupun sosiologis. Secara teologis, pernikahan dapat mendewasakan manusia dalam menjalani pengamalan spiritualnya mendekatkan diri pada Allah SWT. Pasangan suami yang soleh dan istri yang solehah dapat saling memotivasi untuk meningkatkan kualitas ibadah dan membina rumah tangga yang penuh dengan nilai-nilai Islami serta keturunan yang berakhlak mulai. Dari aspek psikologis, salah satu tujuan hidup manusia adalah mencari kebahagiaan, sedangkan pernikahan yang harmonis dan penuh cinta kasih merupakan sarana menciptakan kebahagiaan dan kedamaian yang mendalam di hati manusia. Pernikahan pun merupakan sarana etiklegal untuk menyalurkan kebutuhan biologis manusia sehingga mampu Pemikiran Fikih Maliki Tentang Pernikahan dan Implementasinya dalam UU Perkawinan Aljazair _213 menyelamatkan diri dari seks bebas yang dapat mengakibatkan HIV/ AIDS. Tidak kalah pentingnya, pernikahan memiliki fungsi sosiologis menjalin tali persaudaraan antar dua keluarga yang tak jarang memiliki latar belakang sosio-kultural yang berbeda. Salah satu ayat yang biasanya dikutip dan dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan dalam al-Qur’an adalah:“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang …” (QS. Al-rûm/30: 21). Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Rumah tangga seperti inilah yang diinginkan Islam, yakni rumah tangga sakinah, sebagaimana disyaratkan Allah SWT. dalam surat alRûm (30) ayat 21 di atas. Ada tiga kata kunci yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu sakinah (as-sakînah), mawadah (almawaddah), dan rahmat (ar-rahmah). Ulama tafsir menyatakan bahwa as-sakînah adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan; masing-masing pihak menjalankan perintah Allah SWT. dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi. B.Dasar-Dasar Madzhab Maliki 1. Sekilas Tentang Tokoh dan Periode/Fase Dalam sebuah kunjungan ke kota Madinah, Khalifah Bani Abbasiyyah, Harun Al-Rasyid (penguasa saat itu), tertarik mengikuti ceramah alMuwaththa’ (himpunan hadits) yang diadakan Imam Malik. Untuk hal ini, Khalifah mengutus orang memanggil Imam. Harun al-Rasyîd menunggunya di istananya, sementara Imam Malik menunggu di 214_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 rumahnya. Karena waktu semakin bertambah, dan yang ditunggu tidak datang juga, maka Harun al-Rasyîd pun kemudian memanggilnya, dan berkata: “Wahai Abdallah, seharian aku menunggumu!”. Mendengar hal demikian, Imam Malik menyatakan: “Aku juga menunggumu seharian wahai Amir al-Mu’minin; sesungguhnya ilmu itu dicari, tidak datang sendiri, dan sesungguhnya anak pamanmu SAW. yang dia datang bersama ilmu, jika engkau meninggikannya, dia akan tinggi, dan jika engkau rendahkan, maka ia menjadi rendah.”3 Imam Malik yang bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amîr bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 717 M. Kakeknya bernama Amîr, termasuk salah seorang Sahabat Besar di Madinah. Malik belajar Hadits di bawah bimbingan al-Zuhrî, yang merupakan seorang ulama Hadits terbesar pada masanya, dan juga di bawah bimbingan Perawi Hadits, Nafi’, seorang budak yang dimerdekakan oleh Abdullah ibn ‘Umar. Perjalanan Malik keluar dari Madinah hanya untuk berhaji, karenanya ia mencukupkan diri mempelajari ilmu yang tersedia di Madinah. Dia pernah dipenjara pada tahun 764M. oleh pemerintah Madinah, karena membuat ketetapan hukum yang menyatakan bahwa perceraian yang dipaksa tidak sah. Ketetapan hukum ini bertentangan dengan ketetapan pemerintah, bahwa terdapat sumpah setia yang dari kalangan istri, yang bila mereka melanggar sumpah tersebut, maka otomatis dicerai. Malik kemudian dipenjara dan disiksa, sehingga terdapat cedera di lengannya.Apabila melaksanakan shalat, ia tidak mampu mengangkat tangannya ke dada. Karena itu, menurut beberapa riwayat, Malik kemudian melaksanakan shalat dengan kedua tangan di sisinya.4 Kakek dan ayahnya termasuk kelompok ulama hadits terpandang di Madinah. Karenanya, sejak kecil Imam Malik tak berniat meninggalkan Madinah untuk mencari ilmu. Ia merasa Madinah adalah kota dengan sumber ilmu yang berlimpah lewat kehadiran ulama-ulama besarnya.5 Pemikiran Fikih Maliki Tentang Pernikahan dan Implementasinya dalam UU Perkawinan Aljazair _215 Karena keluarganya merupakan ulama ahli hadits, maka Imam Malik pun menekuni pelajaran hadits kepada ayah dan paman-pamannya. Kendati demikian, ia pernah berguru pada ulama-ulama terkenal seperti Nafi’ bin AbîNu’aim, Ibnu Syihab az Zuhrî, Abul Zinad, Hasyim bin Urwa, Yahya bin Said al Anshari, dan Muhammad bin Munkadir. Gurunya yang lain adalah Abdurrahman bin Hurmuz, tâbi’in ahli hadits, fikih, fatwa dan ilmu berdebat; juga Imam Ja’far Shadiq dan Rabi Rayi. Ciri pengajaran Imam Malik adalah disiplin, ketentraman, dan rasa hormat murid kepada gurunya. Prinsip ini dijunjung tinggi olehnya sehingga tak segan-segan ia menegur keras murid-muridnya yang melanggar prinsip tersebut. Pernah suatu kali Khalifah Mansur membahas sebuah hadits dengan nada agak keras. Sang imam marah dan berkata,”Jangan melengking bila sedang membahas hadits Nabi”. Ketegasan sikap Imam Malik bukan sekali saja. Berulangkali, manakala dihadapkan pada keinginan penguasa yang tak sejalan dengan aqidah Islamiyah, Imam Malik menentang tanpa takut risiko yang dihadapinya. Salah satunya dengan Ja’far, gubernur Madinah. Suatu ketika, gubernur yang masih keponakan Khalifah Abbasysyiah, Al Mansur, meminta seluruh penduduk Madinah melakukan bai’at (janji setia) kepada khalifah. Namun, Imam Malik yang saat itu baru berusia 25 tahun merasa tak mungkin penduduk Madinah melakukan bai’at kepada khalifah yang mereka tak sukai. Ia pun mengingatkan gubernur tentang tak berlakunya bai’at tanpa keikhlasan seperti tidak sahnya perceraian paksa. Ja’far meminta Imam Malik tak menyebarluaskan pandangannya tersebut, tapi ditolaknya. Gubernur Ja’far merasa terhina sekali. Ia pun memerintahkan pengawalnya menghukum dera Imam Malik sebanyak 70 kali. Dalam kondisi berlumuran darah, sang imam diarak keliling Madinah dengan untanya. Dengan hal itu, Ja’far seakan mengingatkan orang banyak, ulama yang mereka hormati tak dapat menghalangi kehendak sang penguasa. 216_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 Namun, ternyata Khalifah Mansur tidak berkenan dengan kelakuan keponakannya itu. Mendengar kabar penyiksaan itu, khalifah segera mengirim utusan untuk menghukum keponakannya dan memerintahkan untuk meminta maaf kepada sang imam. Untuk menebus kesalahan itu, khalifah meminta Imam Malik bermukim di ibukota Baghdad dan menjadi salah seorang penasihatnya. Khalifah mengirimkan uang 3.000 dinar untuk keperluan perjalanan sang imam. Namun, undangan itu pun ditolaknya. Imam Malik lebih suka tidak meninggalkan kota Madinah. Hingga akhir hayatnya, ia tak pernah pergi keluar Madinah kecuali untuk berhaji.6 Pengendalian diri dan kesabaran Imam Malik membuat ia ternama di seantero dunia Islam. Pernah semua orang panik lari ketika segerombolan Kharijis bersenjatakan pedang memasuki masjid Kuffah. Tetapi, Imam Malik yang sedang shalat tanpa cemas tidak beranjak dari tempatnya. Mencium tangan khalifah apabila menghadap di baliurang sudah menjadi adat kebiasaan, namun Imam Malik tidak pernah tunduk pada penghinaan seperti itu. Sebaliknya, ia sangat hormat pada para cendekiawan, sehingga pernah ia menawarkan tempat duduknya sendiri kepada Imam Abu Hanifah yang mengunjunginya. 2. Dari Al Muwaththa’ Hingga Madzhab Maliki Mengenai al-Muwaththa’, Imam Syafi’i berkata:“Tidak ada satu kitab pun di atas permukaan bumi ini yang lebih sahih setelah kitab Allah daripada kitab Malik.”7Mengomentari pendapat Imam Syafi’i di atas, Ibnu Taimiyah menyatakan: “Dan dia (Muwaththa’ Imam Malik) sebagaimana yang dinyatakan Syafi’i RA..”8 Al-Muwaththa’ adalah kitab fikih berdasarkan himpunan haditshadits pilihan. Santri mana yang tak kenal kitab yang satu ini. Ia menjadi rujukan penting, khususnya di kalangan pesantren dan ulama kontemporer. Karya terbesar Imam Malik ini dinilai memiliki banyak keistimewaan. Ia disusun berdasarkan klasifikasi fikih dengan memperinci kaidah fikih yang diambil dari hadits dan fatwa sahabat.9 Pemikiran Fikih Maliki Tentang Pernikahan dan Implementasinya dalam UU Perkawinan Aljazair _217 Al-Muwaththa’ merupakan kitab fikih yang berbeda dari kitab-kitab fikih lainnya, karena mencakupsunnah qawliyyah dan sunnah fi’lliyyah sebagai landasannya, dengan mengikuti sunnah yang memiliki derajat mutawatir, dari masa ke masa.Abu Ameenah Bilal Philips mencatat mengenai al-Muwaththa’: “The early books of Fiqh were usually a mixture of legal rulings, Hadeeths, opinions of the Sahaabah, and of students of the Sahaabah. Al-Muwaththa’ of Imam Malik is a classical example of this stage.”10 Menurut beberapa riwayat, sesungguhnya al-Muwaththa’ tak akan lahir bila Imam Malik tidak “dipaksa” Khalifah Abu Ja’far al-Mansur. Setelah penolakan untuk ke Baghdad, Khalifah al-Mansur meminta Imam Malik mengumpulkan hadits dan membukukannya. Awalnya, Imam Malik enggan melakukan itu, sehingga khalifah berkata: “Ya Abu Abdillah, tidak ada orang yang lebih tahun selain aku dan engkau di atas permukaan bumi ini. Aku disibukkan oleh urusan pemerintahan, maka buatlah sebuah karya yang bermanfaat bagi manusia. Permudahlah manusia dengannya.”11 Berdasarkan ungkapan Khalifah di atas, maka dibuatlah sebuah karya dnegan judul al-muwaththa’, yang berarti al-musahhil wa al-muyassir (yang memberikan kemudahan).12Namun, karena dipandang tak ada salahnya melakukan hal tersebut, akhirnya lahirlah al-Muwaththa’. alMuwaththa’ditulis di masa Abu Ja’far al-Mansur (754-775 M) dan baru selesai di masa al-Mahdi (775-785 M). Dunia Islam mengakui al-Muwaththa’ sebagai karya pilihan yang tak ada duanya. Menurut Syah Walilullah, kitab ini merupakan himpunan hadits paling shahih dan terpilih. Imam Malik memang menekankan betul terujinya para perawi. Semula, kitab ini memuat 10 ribu hadits. Namun, lewat penelitian ulang, Imam Malik hanya memasukkan 1.720 hadits. Kitab ini telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa dengan 16 edisi yang berlainan. Selain al-Muwaththa’, Imam Malik juga menyusun 218_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 kitab al-Mudawwanah al-Kubra, yang berisi fatwa-fatwa dan jawaban Imam Malik atas berbagai persoalan.13 Imam Malik tak hanya meninggalkan warisan buku. Ia juga mewariskan madzhab fikih di kalangan Islam Sunni, yang disebut sebagai Madzhab Maliki. Selain fatwa-fatwa Imam Malik dan Al Muwaththa’, kitab-kitab seperti al-Mudawwanah al-Kubra, Bidâyatul Mujtahid wa Nihâyatul Muqtashid (karya Ibnu Rusyd), Matan al-Risâlah fi al-Fiqh alMaliki (karya Abu Muhammad Abdullah bin Zaid), Ashl al-Madarik Syarh Irsyad al-Masalik fi Fiqh Imam Malik (karya Shihabuddin al Baghdadi), dan Bulgah al-Salik li Aqrab al-Masalik (karya Syeikh Ahmad as SAWi), menjadi rujukan utama madzhab Maliki.14 Di samping sangat konsisten memegang teguh hadits, madzhab ini juga dikenal amat mengedepankan aspek kemaslahatan dalam menetapkan hukum. Secara berurutan, sumber hukum yang dikembangkan dalam Madzhab Maliki adalah al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW., amalan sahabat, tradisi masyarakat Madinah (amal ahli al Madînah), qiyas (analogi), dan al-maslahah al-mursalah (kemaslahatan yang tidak didukung atau dilarang oleh dalil tertentu). Madzhab Maliki pernah menjadi madzhab resmi di Mekah, Madinah, Irak, Mesir, Aljazair, Tunisia, Andalusia (kini Spanyol), Marokko, dan Sudan. Kecuali di tiga negara yang disebut terakhir, jumlah pengikut madzhab Maliki kini menyusut. Mayoritas penduduk Mekah dan Madinah saat ini mengikuti Madzhab Hanbali. Di Iran dan Mesir, jumlah pengikut Madzhab Maliki juga tidak banyak. Hanya Marokko saat ini satu-satunya negara yang secara resmi menganut Madzhab Maliki. Kitab al-Mudawwanah sebagai dasar fiqih madzhab Maliki dan sudah dicetak dua kali di mesir dan tersebar luas disana, demikian pula kitab al-Muwaththa’. Pembuatan undang-undang di mesir sudah memetik sebagian hukum dari madzhab Maliki untuk menjadi standar mahkamah sejarah Mesir.15 Pemikiran Fikih Maliki Tentang Pernikahan dan Implementasinya dalam UU Perkawinan Aljazair _219 Di dalam perkembangan madzhab Maliki, bahwa perkembangan suatu madzhab fikih tidak terlepas dari pembahasan mengenai pemikiran-pemikiran ushul dan banyaknya mashadir yang dimilikinya, dan para penerus setelah Imam mereka, dan juga banyaknya pemikiran hukum yang diijtihadkan. Menurut Abu Zahrah, seluruh hal tersebut terdapat di dalam madzhab Maliki. Manhaj fikih mereka adalah yang paling banyak di antara madzhab-madzhab fikih lainnya.16 Murid-murid Imam Malik telah memperluas pemikiran ushulnya. Di antara muridnya itu ialah ada yang menghimpun antara pemikiran fikih, filsafat, dan hikmah, yaitu Ibnu Rusyd al-Hafîdz, di mana orang-orang Eropa banyak belajar darinya mengenai filsafat Aristoteles. Ia juga pernah menulis sebuah buku yang berjudul Tahâfut al-Tahâfut, merupakan sebuah karya yang berisikan kritikan terhadap pemikiran Tahâfut alFalâsifah karya al-Ghazâlî. Sebagai seorang yang ahli (mumtâz) dalam fikih madzhab Maliki, ia juga ahli dalam bidang komparasi (muqaranah), yang terlihat dalam karya monumentalnya Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, sebuah kajian komparatif dalam bidang fikih.17 Madzhab ini berkembang di berbagai daerah, dan yang paling banyak ialah di daerah Hijaz. Di Madinah, madzhab ini pernah mengalami stagnasi, hingga permasalahan qadha’ dipegang oleh Ibnu Farhoun, tahun 793 H., dan ia memunculkan kembali madzhab ini. Bagaimanapun, dominasinya tidak sebagaimana di daerah Hijaz.18 Madzhab ini juga terlihat di Mesir bahkan ketika Imam Malik masih hidup. Keberadaanmadzhab ini di Mesir tidak terlepas dari peranan murid-muridnya, seperti Abdurrahman ibn al-Qasim,19‘Utsman ibn al-Hakam, Abdurrahman ibn Khâlid, dan Asyhab. Di Mesir, madzhab Maliki paling dominan, sehingga kemudian hadir madzhab Syafi’i, dan akhirnya, Sultan negeri ini menjadi dua madzhab ini sebagai madzhab yang dominandiMesir.20 Di daerah Tunisia juga berkembang madzhab ini, tetapi madzhab Hanafi lebih dominan. Hal ini dikarenakan Sultan Asad ibn al-Farat, 220_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 yang awalnya pengikut madzhab Maliki, berpindah kepada madzhab Hanafi. Kemudian, setelah kedatangan al-Mu’idz ibn Badisy, ia mengajak masyarakat Tunisia untuk mengikuti madzhab Maliki, demikian juga pemerintahannya ikut terlibat di dalamnya, yaitu di daerah Maghrib (Moroko). Hingga sekarang, mayoritas masyarakat Tunisia menganut madzhab ini.21 Di daerah Andalus, madzhab ini memiliki perkembangan yang cukup tajam, karena juga didukung oleh Sultan. Awalnya madzhab yang dominant di daerah ini adalah madzhab al-Awza’i, seorang ahli fikih dari Syam. Kemudian, Sultan tadi itu tidak memberikan wewenang dalam pemerintahan ulama yang tidak fakih dalam madzhab Maliki.22 Berdasarkan penjelasan di atas, Ibnu Hafîzh al-Andalusi sampai menyatakan, bahwa terdapat dua madzhab yang awal perkembangannya didukung oleh Sultan dan pemerintah, yaitu madzhabHanafi di Masyriq, dan madzhab Maliki di Andalus.23Dengan demikian, madzhab Maliki ini berkembang pesat di daerah Islam sebelah Barat, dan sedikit di Timur, seperti di daerah Iraq. Hal ini dikarenakan banyak muridnya yang berada di Mesir dan Tunisia.24 3. Pengendali kekuasaan (otoritas) tasyri’ dan Sumber Tasyri’ Pengendali tasyri’ dalam Madzhab Maliki tidak bisa dipisahkan dari sumber-sumber tasyri’ yang dipegang teguh oleh komunitas madzhab ini. Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa Imam Malik, di samping seorang Faqih, juga seorang Ahli Hadits, dimana dalam meriwayatkan Hadits, Imam Malik menyandarkan periwayatan kepada orang yang menyatakannya, yang merupakan periwayatan yang dhabith. Hal ini dapat dilihat dari kitab al-Muwaththa’.25 Imam Malik memiliki manhaj tersendiri dalam istinbath hukum Islam, akan tetapi manahij tersebut belum tercatat. Kemudian, para muridnya mencatat manâhij tersebut, dan kemudian dijadikan sebagai dasar (ushûl) bagi bangunan pemikiran fikih Imam Malik dan madzhabnya. Qadhi Pemikiran Fikih Maliki Tentang Pernikahan dan Implementasinya dalam UU Perkawinan Aljazair _221 ‘Iyadh di dalam Al-Madarik menjelaskanmengenai dasar-dasar umum yang menjadi manhaj Imam Malik dalam istinbath.26 Secara ringkas, manhaj yang ditempuh di dalam Madzhab Maliki ia mendasarkan pendapat fiqhiyyah pada al-Qur’an; apabila tidak diperoleh informasi pasti dari al-Quran, maka mereka menyandarkannya kepada Sunnah (yang termasuk sunnah di sini ialah Hadits Nabi, Fatwa Sahabat dan keputusan hukum mereka, dan ‘amal penduduk Madinah); kemudian bila masalah belum terlsesaikan dengan berpegang kepada kedua di atas, maka mereka menyandarkan pendapat kepada qiyas (yaitu mencari kesamaan illat antara hukum yang sedang dicari pemecahan [furu’] dengan hukum yang di-nash-kan [ashl]); di samping qiyas, terdapat juga al-mashlahah, sadd al-dzara’i’, al-‘urf, dan al-‘adat.27 Berikut penjelasannya: a. Kitab Allah Imam Malik menjadikan Kitab Allah (al-Qur’an) sebagai dasar bagi hujjah dan dalil terhadap berbagai permasalahan hukum,28 dan sebagai sumber hukum primer yang digunakan tanpa prasyarat dalam berbagai implikasinya.29Dia memahami nash secara sharih, tanpa ditakwil, kecuali ada dalil yang mewajibkannya untuk ditakwil. Di dalam memahami nash, ia menggunakan mafhum al-muwafaqah denganfahw al-khithab, seperti dalam firman-Nya berikut: 30 Artinya:”Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).” (QS. al-Nisa/4:10) Larangan yang terdapat dalam nash dipahami secara fahw al-khithab, yaitu seperti merusaknya, daripada hanya memakannya.31Mereka juga memperhatikan illat hukum, seperti dalam firman-Nya berikut: Artinya:“Katakanlah:‘Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi –karena sesungguhnya semua itu kotor –atau binatang yang disembelih atas 222_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 nama selain Allah’.” (QS. Al-An’am/6: 145). Illat pengharaman yang terdapat di dalam ayat di atas ialah kotor (rijs); yang diartikan sebagai yaitu makanan yang buruk dan sudah terserang wabah penyakit. Dengan demikian, setiap makanan yang termasuk dalam kategori rijs adalah haram juga.32 b. Sunnah Sunnah di dalam madzhab Maliki –sebagaimana madzhab lainnya –dianggap sebagai sumber terpenting kedua di dalam hukum Islam. Yang dimaksud sunnah di sini ialah yang berderajat mutawatir, dan juga masyhur. Madzhab ini juga mengambil dari beberapa perkataan beberapa sahabat yang aman dari dusta, atau riwayat sekelompok tâbi’în yang tidak mungkin bersepakat dusta. Jelasnya, madzhab ini mengambil kemasyhuran sunnah dari masa tâbi’în dan tâbi’ at-tâbi’în. adapun setelah generasi ini tidak dianggap lagi, karena masa-masa tersebut tadi mendekati derajat tawatur dari segi kekuatan istidlal.33 Mereka juga menggunakan Hadits Ahad, yaitu hadits yang tidak sampai derajat mutawatir dan juga masyhur pada masa tabi’in, tidak pula pada masa tabi’in. Dalam hal ini, amal penduduk Madinah lebih didahulukan daripada Hadits Ahad, dan bahkan mereka mendahulukan qiyas daripada Hadits Ahad.34 c. Amal Penduduk Madinah Imam Malik menganggap amal penduduk Madinah sebagai hujjah, apabila amal tersebut di-naql dari Nabi SAW.35 Dia menyebut perkataan gurunya, Rabi’ah ibn Abdirrahman: “Seribu dari seribu orang (perbuatan) lebih baik dairpada satu dari satu orang (periwayatan).”36 Menurut Utsman Syausan, Imam Malik belum menyusun ushul-nya yang dia jadikan sebagai dasar pembinaan fiqh-nya, dan dia juga tidak menjelaskan seluruhnya, hal demikian telah berlangsung antara Imam Malik dengan Imam al-Laits bin Sa’ad dalam isyarat kepada sebagian Pemikiran Fikih Maliki Tentang Pernikahan dan Implementasinya dalam UU Perkawinan Aljazair _223 kaidah-kaidah ushuliyah yang dikeluarkan berdasarkan asas-asasnya, sebagai rincian dari hukum-hukum furu’ sebagaimana tercatat dalam risalahnya “Apabila terjadi suatu hal di Madinah secara dzahir maka diamalkan, dan aku tidak mendapatkan perselisihan di dalamnya; bagi warisan yang terdapat pada mereka yang tidak boleh seorang pun menjiplaknya dan mengakuinya”.37 d. Fatwa Sahabat Imam Malik menganggap fatwa Sahabat di sini sebagai perkataan yang wajib diamalkan. Karena itu terdapat riwayat yang mengenainya bahwa ia mengamalkan fatwa sebagian sahabat dalam manasik haji, dan meninggalkan amalan yang disandarkan pada Nabi SAW. dengan asumsi bahwa apa yang dilakukan sahabat itu tidak sebagaimana anjuran Nabi SAW, dan juga, manasik itu tidak mungkin diketahui melainkan melalui jalan naql.38 Imam Malik mengambil perkataan sahabat dalam suatu perkara yang tidak diketahui kecuali dengan jalan naql sebagai Hadits. Dengan demikian, apabila terdapat pertentangan antara dua ashl, maka ia memiliki di antara keduanya mana yang paling kuat sanadnya dan paling relevan dengan prinsip umum hukum Islam.39 e. Qiyas, Maslahah Mursalah, dan Istihsan Prinsip pemikiran fikih yang dikembangkan oleh Imam Malik ialah mempermudah, dan tidak mempersulit, hal ini sesuai dengan karya monumentalnya al-Muwaththa’, yang berarti mempermudah.40 Apabila qiyas memerlukan pertalian hukum yang tidak di-nash-kan dengan hukum tertentu yang di-nash-kan, maka maslahat particular (almashlahah al-juz’iyyah) mengharuskan selain itu, maka yang demikian inilah yang disebutkan dengan al-istihsan. Dengan kata lain, istihsan ialah ketetapan maslahat karena tidak adanya nash (hukm al-mashlahah haitsu la nash), sama saja apakah pokok permasalahan hukum itu bersumber dari qiyas atau tidak.41 224_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 Ringkasnya ialah bahwa Imam Malik menggunakan hukum maslahat bila tidak terdapat nash al-Quran atau Sunah Nabi SAW. yang menjelaskan perkara yang dimaksud, karena pada prinsipnya, keberadaan syariat Islam ialah demi kemasalahatan manusia. Seluruh nashsyara’, tidak diragukan lagi, berkenaan dengan maslahat. Oleh karena itu, bila tidak terdapat nash mengenai suatu hal, maka hukum maslahat yang benar dan sesuai dengan maksud-maksud syara’ adalah syariat Allah juga.42 f. Al-Dzara’i’ Masalah al-dzara’i’ ini terdapat banyak dalam masalah furu’iyyah, yang sasarannya ialah bahwa sesuatu yang mengarah kepada yang haram maka menjadi haram, sesuatu yang mengarah kepada yang halal maka menjadi halal. Demikian sesuatu yang mengarah pada masalahat maka diajurkan dan dituntut, dan sesuatu yang mengarah kapada mafsadat adalah haram.43 Keberadaan al-dzara’i’ ini merupakan suatu kemestian hukum, dikarenakan suatu perbuatan memiliki implikasi yang berupa tujuan atau maksud tertentu, baik atau buruknya, dapat mendatangkan maslahata atau mafsadat. Perbuatan-perbuatan itu dapat bersifat taklifi (pembebanan), sebagaimana dalam al-ahkam al-khamsah.44 C.Konsep Imam Malik Terhadap Hukum Nikah Madzhab Malikiyyah biasanya membahas dua jenis nikah yaitu nikah yang sah dan nikah yang batal. Nikah dalam malikiyyah adalah sebuah akad yang menghalangi keharaman untuk digauli dengan shigat tertentu.45 Ulama dalam madzhab ini mendefinisikan nikah adalah sebagai akad untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan anak Adam tanpa menyebutkan harga secara pasti sebelumnya. Secara sederhana madzhab malikiyah mengatakan bahwa nikah adalah kepemilikan manfaat karenanya nikah yang sah adalah ketika terkumpul 3 rukunnya, yaitu wali, pengantin dan shigat. 46 Nikah yang Pemikiran Fikih Maliki Tentang Pernikahan dan Implementasinya dalam UU Perkawinan Aljazair _225 sah itu apabila ketiga syarat utama itu terwujud yaitu terbukanya kemungkiinan jima’ karena inti jima’ adalah menumpahkan sperma lakilaki ke rahim sang istri. Syarat kedua adalah terbukanya kemungkinan terjadinya kehamilan. Ketiga, persalinan kelahiran bayi yang mutlak dari rahim sang istri. Hukum nikah dalam madzhab Maliki juga bervariatif.Pertama, Wajib. Hukum menikah menjadi wajib apabila memenuhi tiga syarat, yaitu, khawatir melakukan zina, atau tidak mampu berpuasa atau mampu tapi puasanya tidak bisa mencegah terjadinya zina. Atau tidak mampu memiliki budak perempuan (amal) sebagai pengganti isteri dalam istimta’. Kedua, haram. Hukum menikah menjadi haram apabila tidak khawatir zina dan tidak mampu memberi nafkah dari harta yang halal atau atau tidak mampu jima’, sementara isterinya tidak ridlo. Ketiga, Sunnah. Hukum menikah menjadi sunnah apabila tidak ingin untuk menikah dan ada kekhawatiran tidak mampu melaksanakan hal-hal yang wajib baginya. Keempat, Mubah. Hukum menikah menjadi mubah apabila tidak ingin menikah dan tidak mengharap keturunan, sedangkan ia mampu menikah dan tetap bisa melakukan hal-hal sunnah. Menurut madzhab Maliki, rukun nikah ada lima yaitu : wali, mahar (mas kawin), calon suami, calon istri, dan shighat.47 1. Konsep Mahar menurut Imam Malik Mahar termasuk keutamaan agama Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum wanita dengan memberikan hak yang dimintanya dalam pernikahan berupa mahar kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak karena pemberian itu harus diberikan secara ikhlas. Para ulama fiqih sepakat bahwa mahar wajib diberikan oleh suami kepada istrinya baik secara kontan maupun secara tempo, pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam aqad pernikahan. Para ulama sepakat bahwa mahar merupakan syarat nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.48 226_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 Mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan bukan diartikan sebagai pembayaran, seolah-olah perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang. Pemberian mahar dalam syariat Islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan yang sejak zaman Jahiliyah telah diinjak-injak harga dirinya. Dengan adanya pembayaran mahar dari pihak mempelai laki-laki, status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang diperjual belikan, sehingga perempuan tidak berhak memegang harta bendanya sendiri atau walinya pun tidak boleh dengan semena-mena menghabiskan hak-hak kekayaannya.49 Dalam syariat Islam, wanita diangkat derajatnya dengan diwajibkannya kaum laki-laki membayar mahar jika menikahinya. Pengangkatan hak-hak perempuan pada zaman Jahiliyah dengan adanya hak mahar bersamaan pula dengan hakhak perempuan lainnya yang sama dengan kaum laki-laki, sebagaimana adanya hak waris dan hak menerima wasiat.50 Salah satu keistimewaan Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu dengan memberikan hak untuk memegang dan memiliki sesuatu. Setelah itu, Islam datang dengan menghilangkan belenggu tersebut, kemudian istri diberi hak mahar (maskawin), dan kepada suami diwajibkan untuk memberikan mahar kepada istrinya, bukan kepada ayahnya atau siapapun yang dekat denganya. Dan orang lain tidak boleh meminta harta bendanya walaupun sedikit, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan mendapatkan ridho kerelaan istri.51 Mahar ditetapkan sebagai kewajiban suami kepada istrinya, sebagai tanda keseriusan laki-laki untuk menikahi dan mencintai perempuan, sebagai lambang ketulusan hati untuk mempergaulinya secara ma’ruf.52 Mahar termasuk keutamaan dalam agama Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum wanita dengan memberikan hak yang dimintanya dalam pernikahan berupa mahar perkawinan yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak karena pemberian itu harus diberikan secara ikhlas.53 Pemikiran Fikih Maliki Tentang Pernikahan dan Implementasinya dalam UU Perkawinan Aljazair _227 Terbentuknya sebuah keluarga di awali dari pernikahan antara lakilaki dan perempuan.54 Dalam melaksanakan perkawinan biasanya dirayakan dengan berbagai macam acara, tergantung keinginan kedua mempelai. Islam telah mengangkat derajat kaum wanita, karena mahar diberikan sebagai tanda penghormatan kepadanya. Bahkan andai kata suatu perkawinan itu berakhir dengan perceraian mahar itu tetap merupakan hak milik istri dan suami tidak berhak mengambil kembali kecuali dalam kasus khulu’ yaitu perceraian terjadi karena permintaan istri. Dalam masalah ini istri harus mengembalikan semua mahar yang telah dibayarkan kepadanya.55 Dengan demikian, mahar merupakan hak istri yang diterima dari suaminya, pihak suami memberinya dengan suka rela atas persetujuan kedua belah pihak antara istri dan suami. Pemberian suami dengan suka rela tanpa mengharap imbalan sebagai tanda kasih sayang dan tanggung jawab suami atas istri atas kesejahteraan keluarganya.56 Apabila mahar sudah diberikan suami kepada istrinya, maka mahar tesebut menjadi milik istri secara individual.57 Penyerahan mahar dilakukan secara tunai. Namun apabila calon mempelai wanita menyetujui penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian, maka mahar boleh ditangguhkan. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai pria.58 Undang-undang perkawinan tidak mengatur mengenai mahar. Hal ini karena mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Rukun nikah secara bahasa adalah bagian pokok pada suatu bangunan yaitu bagian terkuat yang menyangga bangunan agar tetap kokoh. Dan menurut istilah adalah apa-apa yang jika sesuatu perbuatan dilaksanakan tidak dengannya akan batal. Pernikahan dianggap sah apabila rukun nikah dan syarat-syaratnya telah terpenuhi. Rukun dan syarat nikah menurut pendapat Ulama’ antara lain adalah: Menurut Abdullah AL-Jaziri dalam bukunya Fiqh A’la Madzâhib AlArba’ah menyebutkan, yang termasuk rukun nikah adalah Al-ijab dan Al-qobul, dimana tidak ada nikah tanpa keduanya.59 Menurut Sayyid 228_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 Sabiq menyimpulkan bahwa rukun nikah terdiri dari Al-ijab dan Alqobul sedangkan yang lainnya termasuk syarat pernikahan. Menurut Imam Hanafi rukun nikah terdiri dari shighât (ijab dan qobul), wali, calon laki-laki, calon perempuan.60 Menurut Imam Syafi’i rukun nikah terdiri dari calon laki-laki, calon perempuan, wali, dua orang saksi, ijab dan qobul.sedangkan menurut Imam Hambali rukun nikah adalah calon laki-laki, calon perempuan, ijab dan qobul.61 Menurut pendapat Imam Hanafi, Imam Syafi’i, Imam Hambali bahwa mahar adalah bukan termasuk rukun nikah. Sedangkan menurut Imam Malik rukun nikah adalah calon laki-laki, calon perempuan, wali, mahar, dua orang saksi, ijab dan qobul. Ketika mahar disebut maka nikahnya sah dan ketika mahar tidak disebutkan maka nikahnya tidak sah. Berdasarkan dengan pendapat Imam Malik bahwa mahar adalah sebagai rukun nikah ini. Adapun pendapat Imam Malik tentang mahar sebagai rukun nikah terdapat dalam kitab AlMuwaththa’ adalah sebagai berikut“rukun nikah ada empat yaitu wali, mahar, tempat, dan ijab qobul”.62 Dari peryataan diatas dapat disimpulkan bahwa Imam Malik berpendapat bahwa mahar adalah sebagai rukun nikah. Tentunya pendapat ini sangat berbeda dengan imam madzhab yang lain, seperti Syafi’i, Hanafi dan Hambali. Dalam permasalah mahar, Maliki mengambil sikap yang sangat berbeda. Perbedaan pandangan Maliki dengan imam madzhab yang lain tentunya memiliki nalar hukum yang berbeda dan tidak digunakan oleh imam madzhab yang lain. Sebelum mengetahui pemikiran Imam Malik seputar status hukum mahar, sebaiknya dibahas terlebih dahulu seputar silang pendapt madzhab mengenai maslah tersebut. Dalam perspektif madzhab, mahar (al-shodâq)63 adalah elemen penting yang menjadi bagian dalam akad nikah. Urgensi posisi mahar dalam nikah, setidaknya bisa dilihat dari munculnya silang pendapat antar madzhab mengenai status hukum mahar dalam nikah. Dalam hal ini, bisa dipetakan dua paradigma Pemikiran Fikih Maliki Tentang Pernikahan dan Implementasinya dalam UU Perkawinan Aljazair _229 madzhab dalam memposisikan status mahar sebagi elemen penting akad nikah. Paradigma pertama, menyatakan bahwa status mahar (al-shodâq) dalam akad nikah merupakan rukun dipandang dari sisi tidak sahnya pensyaratan yang bersifat menggugurkan atau meniadakan (al-isqot) status mahar. Konsekuensi pandangan ini adalah status tidak sahnya akad nikah, apabila disyaratkan dalam akad tersebut peniadaan mahar.64 Pandangan ini adalah pendapat yang dipegang oleh Imam Malik, meskipun sebenarnya masih ada silang pendapat antara ulama madzhab ini sendiri mengenai maslah tersebut. Redaksi kitab-kitab Imam maliki menyatakan mahar adalah rukun. Yang dimaksud dengan rukun dalam hal ini adalah tidak sah sebuah pernikahan apabila dalam akad disyaratkan adanya pengguguran atau peniadaan kewajiban suami untuk membayar mahar kepada istri. Dalamhal ini tidak bisa ditafsirkan, bahwa mahar adalah rukun, sehingga keberadaannya harus disebutkan dalam akad.65 Pada dasarnya, dalam Imam Maliki, mahar yang dianggap sebagai rukun dalam nikah bukan pendapat yang final, tapi masih ada silang pendapat yang cukup kuat mengenai statusnya apakah rukun atau syarat. Faktor-faktor perbedaan pendapat dalam madzhab maliki mengenai status mahar, apakah rukun atau syarat adalah: pertama, pendapat yang menyatakan mahar adalah syarat memandang dari sisi kebaradaan esensi nikah syar’i tercukupi dengan terpenuhinya tiga elemen pokok, yaitu al-mahal (suami dan istri), al-wali, dan al-shighât (ijab dan qobul); kedua, Pendapat yang menyatakan mahar adalah rukun memandang dari sisi sah dan tidak sahnya akad nikah bergantung dari eksitensi mahar yang termasuk elemen pokok dalam nikah, sehingga posisi mahar sama dengan al-mahal (suami dan istri), al-wali, dan al-shighât (ijab dan kabul).66 Paradigma kedua, menyatakan bahwa status mahar dalam akad nikah hanya sebatas syarat sahnya saja, sehingga pensyaratan peniadaan 230_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 mahar dalam akad nikah tidak berfungsi atau tidak bisa diberlakukan. Konsekuensinya adalah wajib bagi suami membayar mahar mitsil (jumlah mahar yang berlaku dalam tradisi keluarganya), jika suami tidak menyebutkan mahar dalam akad nikah. Pendapat ini adalah pandangan mayoritas ulama madzhab. Pasal 14 UU Perkawinan menyebutkan bahwa mahar adalah pemberian yang diberikan kepada istri baik uang atau yang sejenisnya selama diperbolehkan secara syara’. Ia juga adalah sesuatu yang dimiliki secara sepenuhnya. Dalam pasal 15 disebutkan bahwa mahar itu ditentukan dalam akad baik dibayar segera atau ditangguhkan, sementara dalam kondisi nilai mahar itu tidak ditentukan , maka istri berhak mendapatkan mahar mitsil. Dalam pasal 16 dijelaskan bahwa istri berhak menerima maskawin secara penuh baik telah digauli atau karena ditingggal suami yang wafat. Ketika bercerai, ia mendapatkan setengah mahar. 2. Wali Nikah Kata “wali” menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu al-Wali dengan bentuk jamak Auliyâ yang berarti pecinta, saudara, atau penolong. Sedangkan menurut istilah, kata “wali” mengandung pengertian orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi untuk mengurus kewajiban anak yatim, sebelum anak itu dewasa; pihak yang mewakilkan pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan akad nikah dengan pengantin pria). Wali dalam nikah adalah yang padanya terletak sahnya akad nikah, maka tidak sah nikahnya tanpa adanya (wali). Perwalian dalam istilah Fiqh disebut wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan. Yang dimaksud perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.67 Dalam Fiqh Sunnah di jelaskan bahwa wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang Pemikiran Fikih Maliki Tentang Pernikahan dan Implementasinya dalam UU Perkawinan Aljazair _231 hukumnya, wali ada yang khusus dan ada yang umum. Wali khusus adalah yang berkaitan dengan manusia dan harta bendanya.68 Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil suatu pengertian bahwa wali dalam pernikahan adalah orang yang mangakadkan nikah itu menjadi sah. Nikah yang tanpa wali adalah tidak sah. Wali dalam suatu pernikahan merupakan suatu hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya atau memberi izin pernikahannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang lain.69 Pengertian Wali Nikah adalah orang yang memiliki kekuasaan atas seorang wanita untuk melakukan akad apapun, atau karena keturunan, adanya wasiat atas perwalian atas orang Islam.70 Karenanya seorang wali harus disyaratkan beragama Islam, merdeka, cerdas, telah akil balig, tidak sedang berihram dan akadnya tidak haram.71Wali nikah dalam Hukum perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya.Imam Maliki mengharuskan izin dari wali atau wakil terpandang dari keluarga atau hakim untuk akad nikah. Akan tetapi tidak dijelaskan secara tegas apakah wali harus hadir dalam akad nikah atau cukup sekedar izinnya. Meskipun demikian imam malik tidak membolehkan wanita menikahkan dirinya sendiri, baik gadis maupun janda. Sedangkan menurut Malikiah: urutan wali dalam pernikahan adalah: wali mujbir yaitu ayah dan washinya, malik, kemudian setelah wali mujbir yaitu anak laki-laki walaupun dihasilkan dari zina, kemudian anak laki-lakinya anak laki-laki, kemudian ayah (tidak mujbir) dengan syarat ayah dengan cara syar’i (dengan nikah yang sah), saudara lakilaki, saudara laki-lakinya seayah. Waqiila: saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anaknya saudara laki-laki sekandung, anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah, kemudian kakek dari ayah, paman sekandung, anaknya paman, paman dari saudara laki-laki (am liakh), anaknya paman dari saudara laki-laki (ibnu am liakh), ayahnya kakek, pamanya ayah,kemudian perwalian pindah kepada hakim akan tetapi 232_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 dengan syarat tidak diperkenankan meminta bayaran maka apabila memita bayaran tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan terebut. Imam Malik berpendapat juga bahwa jika yang akan menikah adalah orang yang biasa-biasa saja, bukan termasuk orang yang mempunyai kedudukan, kerupawanan dan bukan bangsawanan tidak apa-apa ia menikah tanpa wali. Akan tetapi ketika ia seorang yang berkedudukan, berwajah rupawan dan banyak harta maka ketika menikah harus memakai wali.72 Mengenai persetujuan dari wanita yang akan menikah, imam malik membedakan antara gadis dengan janda. Untuk janda, harus terlebih dahulu ada persetujuan secara tegas sebelum akad nikah. Sedangkan bagi gadis atau janda yang belum dewasa dan belum dicampuri suami, maka jika bapak sebagai wali ia memiliki hak ijbar. Sedangkan wali diluar bapak, ia tidak memilki hak ijbar. Dalam UU Perkawinan pasal 7 disebutkan bahwa wali yang berwenang menikahkan anak wanitanya yang tidak sempurna (al-qashirah)adalah ayah atau salah satu kerabat paling dekat atau qadhi bagi yang tidak ada walinya. Sementara pasal 11 menyebutkan bahwa seorang wanita yang cerdas boleh dinikahi selama dihadiri walinya yaitu ayahnya, salah seorang kerabatnya atau siapapun yang dipilih.73 Lalu bagaimana dengan wali bagi wanita yang telah hamil? Para ulama Maliki, Hambali dan Abu Yusuf dari madzhab Hanafi tidak memperbolehkan pernikahannya itu sebelum dia melahirkan, tidak dengan lelaki yang menzinahinya atau tidak juga dengan lelaki yang lainnya. hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW: ”Seorang wanita yang sedang hamil tidak boleh digauli sehingga dia melahirkan.” (HR. Abu Daud) dan sebagaimana riwayat dari Said al Musayyib bahwa seorang laki-laki telah menikahi seorang wanita dan ketika diketahui bahwa wanita itu sedang hamil dan diberitahukanlah hal ini kepada Nabi SAW maka beliau SAW pun memisahkan mereka berdua.” (HR. Baihaqi). Sedangkan para ulama Syafi’i dan Hanafi membolehkan Pemikiran Fikih Maliki Tentang Pernikahan dan Implementasinya dalam UU Perkawinan Aljazair _233 pernikahannya dikarenakan belum terkukuhkannya nasab, berdasarkan sabda Nabi SAW,” Anak itu bagi yang memiliki tempat tidur sedang bagi yang berzina tidak memiliki apa-apa.” (HR. Jama’ah kecuali Abu Daud). Untuk negara Aljazair adaya wali nikah masih diwajibkan. Jika sang wali tidak mau menikahkan maka bisa diganti wali hakim dengan syarat sekufu. Akan tetapi persoalan sekufu ternyata telah berbeda dengan konsep fikih madzhab. Sekufu dulunya diartikan sebagai kesederajatan dalam hal yang bersifat gengsi dan materialistis seperti dalam nasab, harta, merdeka dan status muslim ternyata berpindah dalam persoalan yang bersifat psikologis sosial seperti adanya rasa cinta dan sudah berhubungan erat. Tentang kebebasan perempuan dalam perkawinan, perundangundangan Aljazair kurang tegas karena disatu sisi melarang adanya nikah paksa, di sisi lain masih diberlakukan adanya hak ijbar.74 Namun pada intinya persetujuan calon diharuskan dan secara implisit mengasumsikan adanya prinsip pelarangan nikah paksa. Kebolehan memaksa nikah (ijbar) bukan alasan semata-mata subyektivitas dari wali (bapak), akan tetapi karena ada argumentasi lain yaitu bila tidak dinikahkan akan terjerumus pada sikap fasad. Pembentukan hukum keluarga di Aljazair diantaranya bermaksud meningkatkan usia nikah bagi kedua calon mempelai. Hukum keluarga 1984 dengan tegas memperlihatkan hal ini. Pada pasal 7 secara jelas ditetapkan usia calon mempelai laki-laki 21 tahun dan calon mempelai perempuan 18 tahun. Usia nikah ini cukup tinggi dibandingkan dengan usia nikah yang terdapat dalam hukum keluarga di negara-negara Islam lain. Tercatat hanya Banglades yang menyamai batas minimum usia nikah.75 Dalam Nash (Al-Qur’an dan Hadist) tidak terdapat ketentuan yang secara ekslipisit menetapkan batasan usia nikah. Para ahli fiqih juga tidak membahas usia nikah. Barangkali melacak pendapat mereka dapat dilakukan dengan mengaitkan usia baligh, karena baligh adalah syarat 234_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 bagi calon mempelai untuk dapat melangsungkan pernikahan. Dalam hal ini, Maliki menetpakan usia 17 tahun. Namun demikian, pernikahan bagi yang masih di bawah usia 17 tahun dianggap sah, kalau menurut wali dapat mendatangkan kebaikan bagi yang bersangkutan.76 Dapat diduga ketentuan usia nikah yang terdapat dalam perundangundangan Aljazair ini murni atas pertimbangan yang lebih bersifat sosiologis, sebab ketentuan ini tidak diambil dari pandangan madzhab di luar Maliki. Madzhab Hanafi yang disinyalir menempati posisi kedua di Aljazair setelah madzhab Maliki, menetapkan usia baligh yang lebih rendah dari batasan ini, yakni 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. 3. Saksi dalam Nikah Diantara madzhab sunni, Malikiyah mempunyai pendapat berbeda tentang saksi dalam pernikahan. Dari pendapat Imam Malik tentang kedudukan saksi dan masa hadirnya saksi dalam perkawinan didukung dengan dalil : ال نكاح:عن عمران بن حصني عن النيب صلي اهلل عليو وسلم قال )بويل وشاىدى عدل (رواه دارالقطىن ّ ّاال Artinya : “Dari Imron bin Husen dari Nabi bersabda : Tiada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil” (HR. Darul Qutni).77 Hadits Imron yang telah diriwayatkan oleh Darul Qutni dan Baihaqi dari segi ilatnya termasuk hadits hasan karena ada salah satu sanad yang tidak disebut yakni Abdullah bin Muhriz. Menurut Malik kehadiran para saksi tidak wajib dalam akad nikah, tetapi hukumnya mandub (sunnah). Dan menurut Imam Malik bahwa saksi harus hadir pada saat persetubuhan antara kedua belah pihak, tanpa adanya saksi maka nikahnya rusak karena ketiadaan kedua saksi itu secara mutlak pembuka jalan kepada zina. Pemikiran Fikih Maliki Tentang Pernikahan dan Implementasinya dalam UU Perkawinan Aljazair _235 Dalam kitab Al-Bahr dari Ali dan ‘Umar dan Ibnu Abbas dan Atroh, Sya’bi, Ibnu Musoyab, Syafi’i, Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal, Tirmidzi berkata : menurut sahabat Nabi dan para tâbi’in mereka berkata bahwasanya tidak ada pernikahan kecuali adanya saksi, dan lafadz tersebut tidak ada perselisihan diantara para ulama. Titik perselisihan itu adalah jika perkawinan hanya disaksikan oleh orang perorang secara tidak bersamaan menurut sebagaian besar ahli ilmu kufah tidak membolehkan, sehingga perkawinan itu harus disaksikan oleh dua orang saksi secara bersamaan pada saat berlangsungnya akad nikah. Menurut sebagaian ulama Madinah boleh persaksiannya seorang demi seorang dengan syarat setelah berlangsungnya perkawinan tersebut harus diumumkan, dan hal ini juga merupakan pendapat Malik. Jadi menurut Imam Malik, kedudukan saksi berfungsi sebagai syarat sah, sehingga pernikahan tanpa adanya saksi maka hukumnya tetap sah asal diumumkan terlebih dahulu. Sebagaimana hadits berikut : “Menyampaikan hadits pada kami Nasr bin Al-Juhsomi dan Halil bin ‘Umar keduanya berkata menyampaikan hadits pada kami Isa bin Yunus dari Kholid bin Ilyas dari Robiah bin Abdurrahman dan dari Qasim dari Aisyah dari Nabi SAW. bersabda: ‘umumkanlah pernikahan dan bunyikanlah genderang’”.(HR. Ibnu Majah).78 Perkawinan merupakan salah satu perbuatan yang menjadi sunnah Rasulullah SAW yang diatur oleh ketentuan syara’, perkawinan adalah satu cara yang sangat tepat untuk melangsungkan keturunan karena salah satu tujuan dari perkawinan adalah mengahasilkan keturunan. Sehingga dalam hal ini perkawinan banyak memberikan maslahat baik bagi para pihak, anak keturunan, orang tua maupun orang-orang di sekitar. Suatu perbuatan akan mempunyai nilai manfaat jika perbuatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik, ketentuan syara’ ataupun aturan-aturan pemerintah dan suatu perbuatan akan bernilai mafsadah jika suatu perbuatan tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan yang masih dan sedang berlaku. 236_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 Imam Malik berpendapat bahwa nikah tanpa dihadiri dua orang saksi tetap sah hukumnya, tetapi dengan sarat pernikahan itu harus diumumkan pada khalayak ramai, sehingga secara tidak langsung bahwa Imam Malik juga melarang nikah sirri. Dalam hal ini dua orang saksi yang berhak mengumumkan tentang telah terjadinya pernikahan antara dua belah pihak. Jadi tanpa adanya dua orang saksi maka kahalayak ramai tidak bisa mengetahui secara pasti tentang berlangsungnya perkawinan. Akan tetapi dalam pandangan ulama’ Malikiyah bahwa saksi harus hadir pada saat persetubuhan kedua belah pihak. Pendapat ini apabila dilihat dari segi moral dan adat istiadat yang berlaku di Indonesia maka kurang relevan, karena pada satu sisi persetubuhan merupakan perbuatan yang sangat privacy (pribadi), yang tidak pantas untuk disaksikan serta tidak mungkin orang lain dapat secara leluasa menyaksikannya. Pada sisi lain kebiasaan tersebut tidak berlaku dalam adat istiadat masyarakat Indonesia. Dan apabila ditinjau dari maslahatnya kesaksian seperti ini hanya sedikit sekali maslahatnya, yakni dua orang saksi hanya dapat mengetahui bahwa antara kedua belah pihak tersebut secara resmi menjadi suami istri yang sah. Dan diantara kedua belah pihak (suami dan istri) sudah tidak berstatus bujang maupun gadis.Dari analisis tersebut sampai pada kesimpulan bahwa pendapat Imam Malik dan ulama Malikiyah dalam konteks bangsa Indonesia kurang relevan, karena hadits yang mendukung pendapat tersebut masih terjadi perselisihan diantara para ulama, apakah yang mendukung itu dhaif, mauqul, mursal ataukah termasuk hadits shahih dan tidak ada pendukung hadits yang masih kuat lagi. Pandangan Malikiyah berangkat dari illat ditetapkannya saksi sebagai syarat sah nikah. Malikiyah mengambil pemikiran bahwa untuk sampainya informasi dan bukti pernikahan tidak harus melembagakan saksi, namun bisa ditempuh melalui i’lan. Malikiyah membedakan i’lan dengan saksi, dimana i’lan difahami sebagai media penyambung Pemikiran Fikih Maliki Tentang Pernikahan dan Implementasinya dalam UU Perkawinan Aljazair _237 informasi dari suatu pernikahan tanpa harus melalui hadirnya sosok saksi dalam proses akad nikah. Menurut Malikiyah saksi tidak dibutuhkan kehadirannya pada saat akad, namun saksi akan diharuskan kehadirannya setelah akad sebelum suami mencampuri isterinya. Malikiyah justru mengutamakan i’lan nikah dari pada kesaksian itu sendiri, karena dalam i’lan sudah mencakup kesaksian. Meski demikian mereka tetap menghadirkan dua orang saksi sebagai wujud pengamalan mereka terhadap hadits tersebut. Hal ini didasarkan pada pandangan Malikiyah, yang benar-benar mengedepankan praktek ahli Madinah yang pada waktu itu mengamalkan hadits-hadits yang berkaitan dengan i’lan. Berbeda dengan Imam Malik, kehadiran saksi dalam akad nikah tidaklah wajib, tetapi cukuplah dengan pemberitahuan (diumumkan) kepada orang banyak. Namun pemberitahuan itu sebelum mereka bercampur. Apabila kedua suami istri itu telah bercampur sebelum disaksikan (diketahui) oleh orang lain, maka keduanya harus dipisahkan (fasakh).Menurut pendapat yang mu’tamad di kalangan Malikiyah (bukan Imam Maliki), saksi menjadi syarat sah suatu perkawinan. Adapun yang menjadi dasar adalah hadits Aisyah, Nabi SAW bersabda: “Tidak sah nikah tanpa wali dan dua orang saksi yang adil”. (HR. Daruquthny dan Ibnu Hibban). Kehadiran saksi pada saat akad nikah amat penting artinya, karena menyangkut kepentingan kerukunan berumah tangga, terutama menyangkut kepentingan istri dan anak, sehingga tidak ada kemungkinan suami mengingkari anaknya yang lahir dari istrinya itu. Juga supaya suami tidak menyia-nyiakan keturunannya (nasabnya) dan tidak kalah pentingnya adalah menghindari fitnah dan tuhmah (persangkaan jelek), seperti kumpul kebo. Berbeda dengan Imam Malik, kehadiran saksi dalam akad nikah tidaklah wajib, tetapi cukuplah dengan pemberitahuan (diumumkan) kepada orang banyak. Namun pemberitahuan itu sebelum mereka 238_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 bercampur. Apabila kedua suami istri itu telah bercampur sebelum disaksikan (diketahui) oleh orang lain, maka keduanya harus dipisahkan (fasakh)79 Dalam referensi lain, menurut Imam Malik:saksi hukumnya tidak wajib dalam akad, tetapi wajib untuk percampuran suami terhadap istrinya (dukhul). Maksudnya, kalau akad dilakukan dengan tanpa seorang saksi pun, akad itu dipandang sah, tetapi bila suami bermaksud mencampuri istrinya, dia harus mendatangkan dua orang saksi. Jika tidak didatangkan saksi, maka akadnya harus dibatalkan secara paksa, dan pembatalan itu sama kedudukannya dengan talak ba’in. Alasan yang dikemukakan Imam Malik, yaitu ada hadits yang dinilainya lebih shahih, diantaranya:“ Diterima dari Malik ibn al-Mundzir, dia berkata ‘sesungguhnya Nabi SAW. Telah membebaskan shafiyah r.a. lalu menikahkannya tanpa adanya saksi “ ( HR Al-Bukhari) Menurut pendapat yang mu’tamad di kalangan Malikiyah (bukan Imam Maliki), saksi menjadi syarat sah suatu perkawinan. Adapun yang menjadi dasarnya adalah hadits dari Aisyah ra., Nabi berkata: “Tidak sah nikah tanpa wali dan dua orang saksi yang adil”. (HR. Dara Quthny dan Ibnu Majah). Jumhur ulama selain Malikiyah berpendapat, bahwa kesaksian itu diperlukan saat akad nikah, agar saksi itu mendengar saat ijab qabul. Lebih lanjut Hanafiyah mengatakan, karena saksi termasuk rukun nikah, maka disyariatkan keberadaannya pada saat akad nikah. Sedangkan Malikiyah berpendapat bahwa saksi memang menjadi syarat sah nikah, tetapi kehadirannya boleh saat akad nikah dan boleh juga disaksikan pada waktu lain seperti resepsi, asal sebelum bercampur kedua mempelai.80 Kehadiran saksi pada saat akad nikah amat penting artinya, karena menyangkut kepentingan kerukunan berumah tangga, terutama menyangkut kepentingan istri dan anak, sehingga tidak ada kemungkinan suami mengingkari anaknya yang lahir dari istrinya itu. Kehadiran saksi dalam akad nikah, adalah sebagai penentu sah akad Pemikiran Fikih Maliki Tentang Pernikahan dan Implementasinya dalam UU Perkawinan Aljazair _239 nikah itu. Saksi menjadi syarat sah akad nikah. Berbeda dengan Imam Malik, kehadiran saksi dalam akad nikah tidaklah wajib, tetapi cukuplah dengan pemberitahuan (diumumkan) kepada orang banyak. Menurut pendapat yang mu’tamad, saksi menjadi syarat sah suatu perkawinan.Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendapat hendaklah dipandang hal yang wajar saja dan hal itu menandakan bahwa pikiran orang itu hidup tidak membeku, kreatif dan tidak mandek berjalan ditempat. 4. Fasakh versi Imam Malik Pemikiran Imam Malik tentang fasakh yaitu kecacatan yang dapat menyebabkan terjadinya fasakh adalah impotensi; gila; karena penyakit sopak dan kusta; dan karena al ritq; al-qorn; al afal dan al-ifdha. Pada dasarnya hukum fasakh adalah mubah atau boleh; apabila istri atau suami yang dicerai dengan keputusan fasakh oleh pengadilan tidak dapat dirujuk Istinbath hukum yang digunakan Imam Malik mengenai fasakh telah memenuhi syarat; artinya telah memakai adillah al ahkam yang paling kuat dengan menempatkan al-Qur’an di urutan pertama; baru kemudian hadits; ijma; dan qiyas Imam Malik telah melakukan kebenaran di dalam istinbath hukum untuk suatu produk hukum; khususnya mengenai fasakh dalam pernikahan. Imam Malik berpendapat bahwa cacat yang dapat menyebabkan batalnya perkawinan ada 9 (sembilan) macam, yaitu: gila, kusta, sopak, tahi keluar ketika bersetubuh, kusta yang terang, potong kemaluan, unnah potong 2 buah pelirnya dan lemah kemaluannya karena penyakit. Menurut, imam Malik (93-179 H/712- 795 M), terjadi pembatalan pekawinan dalam pernikahan fasid (rusak). Beliau merinci beberapa jenis pernikahan yang tergolong pernikahan fasid (rusak) yaitu nikah mut’ah (kawin kontrak) dan pernikahan seorang pria dengan wanita yang mahram (haram dinikahi karena pertalian darah dan hubungan perkawinan). Begitu pula dengan pernikahan seorang wanita tanpa wali, menurut pandangannya bathil (tidak sah). Akan tetapi pernikahan 240_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 yang dianggap fasid (rusak) oleh imam Malik ternyata dianggap sah oleh imam Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M) seperti pernikahan seorang wanita tanpa wali.81 Begitu pula, dalam pernikahan seorang laki-laki dengan mahram-nya (haram dinikahi karena pertalian darah dan hubungan perkawinan), terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama-ulama besar. Menurut imam Malik, Syafi’i, Allaits, Auzai, dan Ahmad, mereka berpendapat pernikahan tersebut tidak sah. Pendapat tersebut juga sesuai pendapat sahabat-sahabat Nabi seperti ‘Umar, Ali, Ibnu ‘Umar dan Zaid bin Tsabit. Dalil yang mereka kemukakan adalah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Usman bin Affan yang artinya:“Jangan menikahi mahrom dan dinikahi, juga tidak boleh meminangnya.” Sedangkan menurut imam abu Hanifah membolehkan pernikahan tersebut terjadi, beliau mengemukakan argumentasinya berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tentang pernikahan Nabi dengan Maimunah yang masih ada hubungan mahrom dengan Nabi. Apabila salah satu dari kedua pasangan suami istri itu murtad (keluar dari agama Islam), maka menurut Madzhab Hanafi telah terjadi talak (cerai) secara langsung. Namun, apabila ada seorang suami yang sebelum menikah dalam keadaan musyrik (penyembah berhala) kemudian masuk Islam dan istri tidak mau masuk Islam mengikuti suaminya maka terjadilah fasakh (pembatalan perkawinan). Adapun jika ada seorang istri masuk Islam dan sang suami tetap dalam kemusyrikannya maka terjadilah talak (cerai), pernyataan ini didasarkan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i. Sedangkan menurut Abu Yusuf pada kasus itu terjadi fasakh (pembatalan perkawinan) tersebut. Lain halnya menurut Ulama Malikiyah, apabila sang suami tidak mau masuk Islam setelah istrinya masuk Islam, atau istri selain kitâbiyah (yahudi dan Nasrani) tidak mau masuk Islam setelah suaminya masuk Islam maka secara langsung rusak ikatan pernikahannya.82 Seseorang yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya dalam jangka waktu tertentu dapat membatalkan perkawinan. Menurut Pemikiran Fikih Maliki Tentang Pernikahan dan Implementasinya dalam UU Perkawinan Aljazair _241 madzhab Maliki, ditunggu sampai empat tahun, jika suami tidak muncul maka ditetapkan iddah (masa menunggu wanita yang ditinggal mati suaminya atau dicerai) yaitu empat bulan sepuluh hari. Setelah itu baru boleh menikah dengan laki-laki lain.83 Dalam UU Perkawinan no 05-09 tanggal 4 Mei 2005 disebutkan bahwa bagi calon mempelai harus menyertakan surat sehat minimal 3 bulan pra pernikahan yang menyebutkan bahwa kedua calon mempelai itu tidak mengidap penyakit atau cacat yang menghalangi kesempurnaan perkawinan. Hanya saja UU Aljazair ini tidak menentukan persis jenis penyakit yang berbahaya atau tidak berbahaya. Dalam pasal di atas juga disebutkan bagi petugas pencatat nikah harus memverifikasi terlebih dahulu surat sehat keduanya sebelum ijab-kabul berlangsung sehingga menghindari adanya penyakit berbahaya yang mungkin mengenai salah satu mempelai, terutama penyakit AIDS. D.Sekilas Dinamika Hukum Keluarga Aljazair Perkembangan hukum Islam dibawah pengaruh Perancis di Aljazair dalam beberapa hal paralel dengan perkembangan hukum Islam dibawah pengaruh Inggris di India, tetapi hasilnya sangat berbeda sekali. Di sebahagian besar wilayah Aljazair qadhi masalah-masalah yang biasanya berada dibawah wewenang mereka. Malahan pemerintahan Perancis memperluas penerapam hukum Islam terhadap adat melampaui apa yang pernah terjadi pada masa Aljazair dibawah kekuasaan Turki.84 Peubahan hukum positif jarang sekali terjadi di Aljazair. Hukum positif di negeri tersebut hanya mencakup masalah-masalah yang bertalian dengan perwalian bagi anak-anak, perkawinan dan perceraian. Pada 4 Februari 1959 (dengan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam dekrit 17 September 1959) yang menetapkan bahwa perkawinan harus dilaksanakan atas persetujuan kedua mempelai, menetapkan batas umur minimum untuk kawin dan mendekritkan bahwa perceraian diputuskan kecuai oleh sebab kematian hanya oleh keputusan pengadilan berdasarkan permintaan suami atau isteri, atau atas permintaan 242_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 keduanya. Pengadilan banding akhir dilaksanakn melalui Muslim Appel Division dari pengadilanbanding di Aljazair. Hukum Perancis juga merupakan faktor yang ikut menentukan dan mempengaruhi bentuk hukum Islam yang berlaku di Aljazair.85 Terutama sekali pengaruh dari pandangan-pandangan hukum para hakim Perancis di Aljazair, khususnya Marcel Movand (meninggal 1932) yang mengepalai komisi penyusunan konsep hukum Islam Aljazair pada tahun 1906 yang hasilnya diterbitkan pada tahun 1916. komisi tersebut mengadakan perubahan-perubahan hukum madzhab Maliki, dan mengambil ajaran-ajaran Madzhab Maliki apa dirasa lebih sesuai dengan ide-ide modern. Code Morand ini memang tidak pernah menjadi hukum tetapi mempunyai arti yang sangat penting. Dengan cara ini hukum Islam yang berlaku di Aljazair telah menjadi sistem hukum yang independen yang disebut:“Droit Musulman Algerien”. Tidak terdapat komperatif studi lainnya yang dilakukan untuk mempelajari perbedaan caranya teori hukum Inggeris dan Perancis mendekati masalah-masalh hukum Islam. Tiga tahun sebelum proklamasi kemerdekaan, pemerintahan Aljazair megumumkan sebuah hukum yang ringkas yang disebut Marriage Ordinance 1959. tujuan lahirnya undang-undang ini adalah untuk mengatur aspek-aspek tertentu dari perkawinan dan perceraian di kalangan umat Islam. Ordonansi ini memuat 12 ayat yang tujuan utamanya adalah: 1. Mengatur tata cara pelaksanaan dan registerasi perkawinan. 2. Meningkatkan usia nikah calon suami maupun isteri. 3. Mengatur perceraian melalui peradilan dan ketentuan-ketentuan pasca perceraian. Menindak lanjuti proklamasi kemerdekaan pada bulan Juli 1963, Aljazair mempermaklumkan sebuah konstitusi yang menempatkan Islam sebagai agama negara.86 Sebagai negara jajahan Perancis, sistem hukum Aljazair terpengaruh oleh sistem hukum Perancis dalam hukum Pemikiran Fikih Maliki Tentang Pernikahan dan Implementasinya dalam UU Perkawinan Aljazair _243 sipil, pidana dan administrasi peradilan. Tetapi hal ini tidak menafikan hukum keluarga bermadzhab Maliki dan Ibadi yang khas lokal. Ketika negara ini dalam masa penajajahan, usaha-usaha priodik mensistemisasi dan mengkodifikasikan bagian-bagian hukum keluarga telah dilakukan dibawah panduan para ahli hukum Islam. Pada tahun 1906 seorang ahli hukum Perancis bernama Marcel Morand diberi wewenang untuk mempersiapkan rancangan hukum Islam, khususnya hukum keluarga sesuai dengan yang berlaku pada perdilan lokal. 87 Draft tersebut dipublikasikan 10 tahun kemudian dibawah titel:“Avant-Project de Code du Droit Musulman Algerien”. Sekalipun secara umum didasarkan pada madzhab Maliki, prinsip-prinsip hukum non-Maliki yang sebagaian besarnya madzhab Hanafi ikut mewarnai rancangan undang-undang ini, sebab pengikut madzhab Hanafi menduduki urutan kedua setelah Maliki. Hasil usaha Morand tersebut tidak pernah dijadikan hukum positif lewat legislasi formal hukum, namun dapat dicatat rancangan ini memberi pengaruh pada aplikasi dan administrasi hukum keluarga Islam di Aljazair.88 Segera setelah mencapai kemerdekaan Aljazair mengundangkan sebuah hukum untuk mengamandemen ordonansi 1959 dan mencabut ketentuan-ketentuan yang mengatur usia nikah. Di sampng itu, hukum baru tersebut juga mencabut aturan-aturan yang mengharuskan penganut Ibadi mengikuti ordonansi tersebut. Dengan amandemen ini berarti ketentuan hukum yang tetap berlaku setelah tahun 1963 mengikat bagi keseluruhan warga negara. Setelah diundangkannya kostitusi tahun 1976, tuntutan kodifikasi hukum keluarga dan waris yang komfrehensif semakin meningkat. Untuk tujuan ini, pada tahun 1980 telah diajukan sebuah rancangan hukum dimaksud kepada Dewan Nasional. Beberapa tahun kemudian, setelah melewati perdebatan dan pertimbangan rancangan tersebut diterima dan ditetapkan pada tahun 1984. Aturan-aturan yang termaktub didalamnya diambil dari beberapa aliran fiqh, rancangan hukum keluarga Aljazair 1916 dan hukum keluarga yang berlaku di negra lain, khususnya Maroko. 244_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 Undang-undang keluarga di Aljazair masih mendasarkan secara normatif terhadap teks-teks al-Quran walaupun dengan penafsiran sosiologis yang relevan dengan konteks sekarang, kedua mendasarkan pada siyâsah shar’iyyah berupa adanya sanksi denda dan pidana bagi mereka yang melanggar atau persyaratan administratif ijin poligami dengan persetujuan isteri sebelumnya dan anutan madzhab masyarakat yang terus diikuti sebagai kasus wali nikah. Adapun metode pembaharuan hukum di beberapa negara modern dengan cara 1) tahsis al-qada/siyasah shar’iyyah seperti persyaratan dalam poligami dengan izin dari istri sebelumnya 2) reinterpretasi teks dengan jalan qiyas seperti kasus poligami dan asas hukumnya dan 3) takhayyur dan talfîq, seperti dalam penghapusan hak ijbar dengan mengambil pendapat Ibn Subrumah.89 1. Nikah Beda Agama Salah satu isu penting dalam materi pembaharuan hukum keluarga di negara-negara Muslim adalah perkawinan beda agama. Meskipun materi ini tidak banyak dibahas dalam Undang-undang Hukum Keluarga di negera-negara Muslim, tetapi tingkat signifikansinya begitu jelas jika dikaitkan dengan tingkat kemajemukan agama yang dianut warga negara di setiap negara-negara Muslim dan tingkat perubahanperubahan sosial dan politiknya.Pengaturan perkawinan beda agama yang diatur dalam Undang-undang Hukum Keluarga Irak, Yaman Utara, Aljazair, dan Yordania sesungguhnya merupakan upaya negara dalam memberikan kejelasan status hukum di tengah perdebatan di kalangan Muslim (fuqaha dan mufasir) sejak zaman klasik hingga sekarang tentang hukum perkawinan beda agama.Adapun menurut madzhabMâlikî, menikahi Ahl al-Kitâb hukumnya adalah makruh. Madzhab Hanbalī menyatakan menikahi Ahl al-Kitâb adalah khilāf yang utama karena ‘‘Umar ibn al-Khattāb pernah mengatakan kepada para sahabat yang menikahi wanita Ahl al-Kitâb yang berstatus dhimmī agar menceraikannya. Para sahabat pun menceraikan istri-istri dari Ahl alKitâb, kecuali Khudhayfah. Adapun Ahl al-Kitâb yang berstatus ‘arbî, Pemikiran Fikih Maliki Tentang Pernikahan dan Implementasinya dalam UU Perkawinan Aljazair _245 menurut madzhab hanafî haram hukumnya menikahi mereka apabila berada di dār al-’arb. MadzhabSyâfi’î dan Mâlikî berpendapat haram hukumnya. 90 Perkawinan beda agama di Aljazair diatur dalam Undang-undang Hukum Perdata No. 11 tahun 1984 (Civil Code).91 Pasal 31 menyebutkan, “Seorang perempuan Muslimah tidak dapat menikah dengan seorang laki-laki non-Muslim.” Pasal ini menegaskan bahwa adanya larangan perempuan Muslimah dinikahkan dengan laki-laki non-Muslim. Hal ini tentu saja tidak berbeda dengan pandangan kebanyakan ulama yang bersepakat kebolehan laki-laki menikah dengan Ahl al-Kitâb dan sebaliknya dilarang perempuan menikah dengan non-Muslim. MadzhabMâlikî yang dianut mayoritas masyarakat Aljazair berpendapat bahwa menikahi wanita Ahl al-Kitâb adalah makruh, seperti halnya pendapat madzhab fikih lainnya, seperti madzhab hanafî dan Syâfi’î. Inilah letak perbedaan antara materi hukum perkawinan beda agama dalam Hukum Keluarga di Aljazair dengan pendapat madzhabMâlikî. Aturan perkawinan beda agama di Aljazair hanya diatur satu pasal tentang perempuan Muslimah yang dilarang menikah dengan laki-laki non-Muslim. Ini berarti laki-laki Muslim boleh menikahi wanita Ahl alKitâb. Ketentuan ini tidak menjelaskan status perempuan yang telah menikah dengan laki-laki non-Muslim, apakah dibatalkan atau tidak. Hukum perkawinan beda agama yang diberlakukan di Aljazairsesungguhnya menunjukkan arus perdebatan yang serius dari keterikatan dengan tekstual Al-Qur’an (kebolehan laki-laki Muslim menikah dengan wanita Ahl al-Kitâb) dengan mengambil jalan istinbāt lain (larangan laki-laki Muslim menikah dengan wanita Ahl al-Kitâb). Negara ini berani tidak merujuk pada pendapat imam-imam madzhab (Mâlikî, hanafî, dan Syâfi’î) yang sepakat menghukumi makruh bagi laki-laki Muslim yang menikah dengan wanita Ahl al-Kitâb. Argumen sadd al-dharī’ah atau al-maslahah yang biasanya digunakan untuk melarang laki-laki Muslim menikah dengan wanita Ahl al-Kitâb 246_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 tidak menjadi pertimbangan utama, sehingga hukum perkawinan beda agama dibiarkan seperti bunyi teks Al-Qur’an. Kecenderungan ini bukan berarti representasi dari liberalisme Islam, yang cenderung membolehkan laki-laki Muslim menikah dengan wanita Ahl al-Kitâb. Tetapi juga, kecenderungan ini tidak memenuhi kepentingan konservatisme dan radikalisme Islam. Dengan demikian, hukum perkawinan beda agama di Yaman Utara, Yordania, Aljazair, dan Irak cenderung bertahan dengan tekstualitas al-Qur’an tanpa pernah dipengaruhi oleh radikalisme dan liberalisme Islam. Meskipun tidak dominan, pemberlakuan hukum perkawinan beda agama di Yaman Utara, Yordania, Aljazair, dan Irak tetap menggunakan pertimbangan yang kompleks, seperti konteks sosial-politik gerakan Islam, kolonialisme, pendapat imam-imam madzhab, dan teks terutama al-Qur’an. Ini berarti bahwa perdebatan pemberlakuan hukum perkawinan beda agama di suatu negara akan sangat beriringan dengan kompleksitas yang dialami oleh negara dalam mengelola perbedaan ideologi, sosial, dan politik. 2. Pembatasan Usia Perkawinan Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. al-Quran mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Secara tidak langsung, al-Quran dan Hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria,ihtilam bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap baligh.92 Ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah menyatakan Pemikiran Fikih Maliki Tentang Pernikahan dan Implementasinya dalam UU Perkawinan Aljazair _247 bahwa anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun. Ulama Hanafiyyah menetapkan usia seseorang dianggap baligh bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan. Sedangkan ulama dari golongan Imamiyyah menyatakan bahwa Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan. Terhadap anak perempuan yang berusia 9 tahun, maka terdapat dua pendapat. Pertama, Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa anak perempuan yang berusia 9 tahun hukumnya sama seperti anak berusia 8 tahun sehingga dianggap belum baligh. Kedua, ia dianggap telah baligh karena telah memungkinkan untuk haid sehingga diperbolehkan melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada hak khiyar baginya sebagaimana dimiliki oleh wanita dewasa. Mengingat, perkawinan merupakan akad/perjanjian yang sangat kuat (miitsaqan ghalizan) yang menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan. Pembentukan hukum keluarga di Aljazair diantaranya bermaksud meningkatkan usia nikah bagi kedua calon mempelai. Hukum keluarga 1984 dengan tugas memperlihatkan hal ini. Pada pasal 7 secara jelas ditetapkan usia calon mempelai laki-laki 21 tahun dan calon mempelai perempuan 18 tahun. Usia nikah ini cukup tinggi dibandingkan dengan usia nikah yang terdapat dalam hukum keluarga di Negara-negara Islam lain. Tercatat hanya Banglades yang menyamai batas minimum usia nikah. Dalam Nash (al-Qur’an dan Hadits) tidak terdapat ketentuan yang secara ekslipisit menetapkan batasan usia nikah. Para ahli fiqih juga tidak membahas usia nikah. Barangkali melacak pendapat mereka dapat dilakukan dengan mengaitkan usia baligh, karena baligh adalah syarat bagi calon mempelai untuk dapat melangsungkan pernikahan. Dalam hal ini, Maliki menetapkan usia 17 tahun. Namun demikian, pernikahan 248_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 bagi yang masih di bawah usia 17 tahun dianggap sah, kalau menurut wali dapat mendatangkan kebaikan bagi yang bersangkutan.93 Dapat diduga ketentuan usia nikah yang terdapat dalam perundangundangan Aljazair ini murni atas pertimbangan yang lebih bersifat sosiologis, sebab ketentuan ini tidak di ambil dari pandangan madzhab di luar Maliki. Madzhab Hanafi yang disinyalir menempati posisi kedua di Aljazair setelah madzhab Maliki, menetapkan usia baligh yang lebih rendah dari batasan ini, yakni 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.Jadi, dalam batasan usia nikah Aljazair melakukan reformasi extra dektrinal, yaitu keluar dari pendapat yang berkembang di kalangan pemikir hukum Islam (madzhab), seterusnya membuat keputusan hukum baru melalui ijtihad, dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam.Aturan usia nikah 20 tahun bagi laki-laki, 28 tahun bagi perempuan dapat saja diabaikan hakim atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan dan atas pertimbangan demi kebaikan para calon. E. Penutup Pemikiran madzhab Maliki di Aljazair sebagai madzhab mayoritas tentu sangat mempengaruhi pola pemikiran UU Keluarga di Negara tersebut. Namun tentu saja madzhab-madzhab lainnya pun dalam batas tertentu turut serta menyuburkan dialektika fikih ini. Kecenderungan maliki yang tekstualis ini tentu sangat relevan dengan kultur masyarakat tradisonalis yang masih menjadi mainstream. Hukum keluarga di Aljazair memang sangat dipengaruhi madzhab maliki walaupun tetap mengadopsi juga madzhab lainnya. Upaya modifikasi hukum ini sudah banyak dilakukan terutama menyikapi permasalahan-permasalahan modern yang terjadi. Kehadiran universitas-universitas Islam banyak mewarnai dinamika hukum ini sehingga memungkinkan terwujudnya upaya kodifikasi hukum yang lebih komprehensif. Dinamika ijtihad modern mutlak diperlukan agar bisa menjawab tantangan maslah yang terjadi. Pemikiran Fikih Maliki Tentang Pernikahan dan Implementasinya dalam UU Perkawinan Aljazair _249 Kehadiran hukum keluarga dalam perkembangannya sangat membantu upaya penyelesaian masalah kontemporer. Elastisitas hukum Islam sebagai ciri fundamentalnya memungkinkan adanya tajdîd atau pembaharuan yang bermanfaat bagi pengayaan tema-tema terkait hukum keuarga. Tipikal hukum keluarga di Aljazair ini bisa jadi barometer bagi tajdîd dalam hukum keluarga di indonesia. Tentu saja upaya sinergis dari berbagai praktisi hukum Islam sangat dibutuhkan. 250_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 Daftar Pustaka Abu Zahrah,Muhammad,Târîkhal-Madzâhib al-Islâmiyyah fi al-Siyâsah wa al-Aqa’id wa Târîkhal-Madzâhib al-Fiqhiyyah, Kairo:Dar al-Fikr al‘Arabi, tt., cet. 1, Al-Azhar Khuzairi, Thahir, al-Madkhal il al-Muwaththa’ Imam Malik ibn Anas, Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah, Maktabah al-Syu’un al-Fanniyyah,1429H./2008M, cet. 1 Al-Dardir, Syarh Ash-Shagîr tt., juz 2. Al-Jaziri, Abd al-Rahman bin Muhammad ‘Audh, al-Fiqh ‘ala al-Madzâhib al-`Arba’at, Beirut:Dar Ibn Hazm, 2001. Al-Dasyuqi, Hasiyah Al Dasuqy, Bairut:Dar Fikr al-Ilmiyah, 2009, Vol 2. Al-Jaziri, Abdurrahman, Fiqh A’la Madzâhib Al-Arba’ah, Semarang:CV. Toha Putra, 1993. Ali al-Sayis, Muhammad, Nasy’ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa Athwaruh,AlAzhar:Majma’ al-Buhuts al-Islamiyyah, al-Kitab al-Tasi’, tt. Ameenah Bilal Philips, Abu, The Evolution of FIqh:Islamic Law and The Madh-hab, Kuala Lumpur:A.S. Noordeen, 1411H./1990M, cet. 2. Asy-Syaukani, Muhammad Ibnu Ali Mahmud, Syarh Nailul Author, Beirut: Dar Al-Fikr,t.th, Juz 6. Daly, Peunoh,Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam, Jakarta:PT Bulan Bintang, 1998. Dutton, Yasin, The Origin of Islamic Law:The Quran, tha Muwaththa’, and Madinan ‘Amal,Richmond Survey:Curzon Press, 1999, cet. 1. Fuad Abd al-Baqi,Muhammad,al- Mu’jam al- Mufahras li al-Fâz al-Qurân al- Karîm, Beirut:Dar al-Fikr, 1987. Pemikiran Fikih Maliki Tentang Pernikahan dan Implementasinya dalam UU Perkawinan Aljazair _251 Ghazali, Abd. Rahman, Fiqih Munakahat , Jakarta:Prenada Media, 2003. Hakim, Rahmat, Hukum Perkawinan Islam, CV. Pustaka Setia, 2000. Husain,Muhammad, Fiqih Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender,Yogjakarta: LKIS, 2001. I.Doi, Abdur Rahman, Perkawinan dalam Syari’at Islam, Jakarta:PT Rineka Cipta, 1992. Jawad Mughniyyah, Muhammad, al Ahwâl al Syakhsiyyah, Beirut:Dar al ‘Ilmi lil Malayain, tt. Mahmood, Tahir, Personal Law in Islamic Countries, New Delhi:Academy of Law and Religion, 1987. M. Ali Hasan, perbandingan Madzhab fiqh, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2000, cet 2. Muzdhar, M. Attho’, Membaca Gelombang Jihad, antara Tradisi dan Liberalisasi, Yokyakarta:Titian Ilahi Pres, 1998. Muhtar, Kamal,Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan,Jakarta:Bulan Bintang, 1994. N.J Coulson,MA, Aljazair History of Islamic Law, Edinburgh:Edinburgh University, 1964. Nasution, Khoiruddin, Status Wanita di Asia Tenggara, Jakarta-Leiden:INIS, 2002. Nurudin, Amin, Hukum Perdata Islam di Indonesia Jakarta:Prenada Media, 2004, cet 1. Nur, Djamaan, Fiqih Munakahat, Semarang:Dina Utama Semarang, 1993. Rofiq, Ahmd, Hukum Islam Di Indonesia Jakarta:Raja Grafindo Persada 2003. Rusyd, Ibnu, Terjemah Bidâyatul Mujtahîd, Penerjemah:M. A. Abdurrahman dan A. Harits Abdullah, Semarang:CV. Asy. Syifa’, 1990. 252_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 Sabiq, Sayyid,Fiqih Sunnah 2, Ter. Nor Hasanudin, Jakarta:Pena Pundi Aksara 2006, Cet 1. ---------------, Fiqh Sunnah 7, Bandung:Al-ma’arif, 1997. Schacht, Joseph, Pengantar Hukum Islam, terj., Depag., 1985. Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta:PT Rineka Cipta, 2005. Syarifuddin, Amîr,Ushul Fiqh, Jakarta:Kencana, 2009, cet. 5, vol. 2. Syausyan, Utsman bin Muhammad al-Akhdhar, Takhrîj al-Furu’ ‘ala al-Ushûl:Dirâsah Târîkhiyyah wa Manhajiyyah wa Tathbiqiyyah, Riyadh:Dar Thayyibah, 1419H./1998M., cet. 1, vol. 1. Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat, Jakarta:Rajawali Pers, 2010. Wahhab Khollaf, Abdul,Khulâshah Târîkh tasyri’ Islam, Solo:CV. Ramadhani, 1991. Zakariya al Kandahlawi, Maulana, al Muwaththa”tt. Zuhaily,Wahbah, Al Fiqhul Islami wa ‘Adilatuhu, Beirut:Daar al Fikr, juz 2. Pemikiran Fikih Maliki Tentang Pernikahan dan Implementasinya dalam UU Perkawinan Aljazair _253 Endnotes 1. Muhammad Fuad Abd al-Baqi,al- Mu’jam al- Mufahras li al-Faz al- Quran alKarim, Beirut: Dar al-Fikr, 1987: h. 332-333 dan 718. 2. Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, CV. Pustaka Setia, 2000, h. 13. 3. Thahir al-Azhar Khuzairi, al-Madkhal il al-Muwaththa’ Imam Malik ibn Anas,Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah, Maktabah alSyu’un al-Fanniyyah, 1429H./2008M, cet. 1, h. 25-26. 4. Abu Ameenah Bilal Philips, The Evolution of FIqh: Islamic Law and The Madhhab, Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1411H./1990M, cet. 2, h. 69-70; Yasin Dutton, The Origin of Islamic Law: The Quran, tha Muwatta’, and Madinan ‘Amal,Richmond Survey: Curzon Press, 1999, cet. 1, h. 11;. 5. Yasin Dutton, ibid.,h. 11-12. 6. Abu Ameenah Bilal Philips, ibid, h. 70. Menurutnya, Imam Malik mencukupkan diri dengan pengetahuan yang terdapat di Madinah. 7. Thahir al-Azhar Khuzairi, ibid, h. 6. 8. Ibid 9. Yasin Dutton, ibid, h. 22. 10. Abu Ameenah Bilal Philips, ibid, h. 57. 11. Thahir al-Azhar Khuzairi, ibid, h. 74-75. 12. Ibid., h. 75. 13. Yasin Dutton, ibid, h. 31. 14. Abdul Wahhab Khollaf, Khulashoh Tarikh tasyri’ Islam, Solo: CV. Ramadhani, 1991, h. 89; lih. juga dalan Yasin Dutton, ibid., h. 31. 15. Abdul Wahhab Khollaf, ibid. 16. Muhammad Abu Zahrah, Tarikh al-Madzâhib al-Islamiyyah fi al-Siyasah wa al- 254_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 Aqa’id wa Tarikh al-Madzâhib al-Fiqhiyyah, Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.t.,cet. 1, h. 404. 17. Muhammad Abu Zahrah, ibid, h. 404. 18. Ibid., h. 405. 19. Abdurrahman ibn Qasim ini dilahirkan di Madinah, seorang yang ahli dalam bidang Hadits dan qira’ah. Dia menulis sebuah kitab monumental dalam mazhab Maliki, yaitu Al-Mudawwanah. Lih. Abu Ameenah Bilal Philips, ibid,, h. 73-74. 20. Muhammad Abu Zahrah, ibid, h. 405. 21. Ibid. 22. Ibid. 23. Ibid. 24. Ibid. 25. Ibid h. 396. 26. Ibid. 27. Muhammad Ali al-Sayis, Nasy’ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa Athwaruh Al-Azhar: Majma’ al-Buhuts al-Islamiyyah, al-Kitab al-Tasi’, t.t., h. 96. 28. Muhammad Abu Zahrah, ibid, h. 397. 29. Abu Ameenah Bilal Philips, ibid, h. 71; Yasin Dutton, h. 61. 30. Muhammad Abu Zahrah, ibid, h. 397; Yasin Dutton, ibid, h. 114-115. 31. Muhammad Abu Zahrah, ibid., h. 397. 32. Ibid., h. 398. 33. Zakariya al-Sibri, ibid, h. 36; Abu Umar Yusuf al-Andalusi, ibid, h. 10. 34. Muhammad Abu Zahrah, ibid, h. 399. 35. Yasin Dutton, ibid, h. 33. Pemikiran Fikih Maliki Tentang Pernikahan dan Implementasinya dalam UU Perkawinan Aljazair _255 36. Muhammad Abu Zahrah, ibid, h. 399. 37. Utsman bin Muhammad al-Akhdhar Syausyan, Takhrij al-Furu’ ‘ala al-Ushul: Dirasah Tarikhiyyah wa Manhajiyyah wa Tathbiqiyyah, Riyadh: Dar Thayyibah, 1419H./1998M., cet. 1, vol. 1,h. 138-139. 38. Muhammad Abu Zahrah, ibid, h. 400; Zakariya al-Sibri, ibid, h. 82-83. 39. Ibid. 40. Thahir al-Azhar Khuzairi, ibid,h. 75. Al-muwaththa’, yang berarti al-musahhil wa al-muyassiryang memberikan kemudahah, Lih. juga Abdul Halim alJundi, ibid, h. 200. 41. Muhammad Abu Zahrah, ibid, h. 401. 42. Muhammad Ali al-Sayis, ibid, h. 97; ‘Adil al-Syuyikh, ibid, h. 226. 43. Muhammad Abu Zahrah, ibid, h. 402. 44. Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, vol. 2, Jakarta: Kencana, 2009, cet. 5, h. 421422. 45. Al-Dardir, Syarah Ash-Shagir juz 2, h. 332. 46. Al-Dardir, Syarah Ash-Shagir juz 2, h. 334. 47. Abd al-Rahman bin Muhammad ‘Audh al-Jaziri, al-Fiqh ‘ala al-Madzâhib al`Arba’at, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2001, h. 818. 48. Ibnu Rusyd, Terjemah Bidayatul Mujtahid, Penerjemah: M. A. Abdurrahman dan A. Harits Abdullah, Semarang: CV. Asy. Syifa’, 1990, h. 385. 49. Sayyid sabiq, Fiqih Sunnah 2, Ter. Nor Hasanudin, Jakarta: Pena Pundi Aksara 2006, Cet 1, h. 40. 50. Amin Nurudin, Hukum Perdata Islam di IndonesiaJakarta:Prenada Media, 2004, cet 1, h. 54. 51. Abd. Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat,”seri buku daras”, Jakarta: Prenada Media, 2003, h. 84-85. 52. Muhammad Husain, Fiqih Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan 256_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 Gender,Yogjakarta: LKIS 2001, h.108-109. 53. Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h.38. 54. Kamal Muhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan,Jakarta: Bulan Bintang, 1994, h.81. 55. Abdur Rahman I.Doi, Perkawinan dalam Syari’at Islam, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992, h.64. 56. Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1998, h.219. 57. Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005, h.55. 58. Ahmd Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia Jakarta:Raja Grafindo Persada 2003 h. 104. 59. Abdurrahman Al-Jaziri, Fiqh A’la Madzahib Al-Arba’ah, Semarang: CV. Toha Putra, 1993, h.20. 60. Abdurrahman, Ghazali, Fiqih Munakahat, Jakarta: 2008, h.127. 61. Raja’ Ahmad Ahmad, Diktat kuliyah Dirasah Islamiyah wa al-Arabiyyah li’l Banat, h. 72. 62. Maulana Zakariya al Kandahlawi, al Muwaththa’‟t.t, h. 287. 63. Pada dasarnya istilah mahar tidak dikenal dalam sumber asli hukum Islam. Al-quran dalam beberapa kesempatan hanya menyebutnya sebagai sadaqah. yaitu dalam surat al-Nisa’ 4:4 “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dan maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yangsedap lagi baik akibatnya”. 64. Al-Dasyuqi, Hasiyah Al-Dasuqy, Bairut: Dar Fikr al-Ilmiyah, 2009, Vol 2, h. 294. Pemikiran Fikih Maliki Tentang Pernikahan dan Implementasinya dalam UU Perkawinan Aljazair _257 65. Ibid, h. 14. 66. al-Showi, Hasiyah Al Showi, h. 79. 67. Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, h. 89. 68. Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 7, Bandung: Al-ma’arif, 1997, h. 11. 69. Djamaan Nur, Fiqih Munakahat, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993, h. 65. 70. Ahkam NIkah inda al-Malikiyyah, h. 172. 71. Ibid h. 174. 72. Ibid, h. 189. 73. Ibid, h. 183-184. 74. Lihat UU Keluarga al Jazair dalam Ahkam an Nikah, h. 34. 75. M. Attho’ Muzdhar, Membaca Gelombang Jihat, antara Tradisi dan Liberalisasi, Yokyakarta: Titian Ilahi Pres, 1998, h. 179 76. Abdur Rahman al-jaziri, al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba’ah, Solo: Toko Kitab AS, ttp., juz IV, h. 52. 77. Muhammad Ibnu Ali Mahmud Asy-Syaukani, Syarah Nailul Author, Beirut:Dar Al-Fikr,t.th, Juz 6,h. 2-8. 78. Muhammad Fuad Abdul Baqi, Sunan Ibnu Majah, Beirut: Dar Al-Fikr, t.th, Juz I,h. 611. 79. M. Ali Hasan, perbandingan mazhab fiqh, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000, cet 2, h. 145-149. 80. Ibid. 81. Zuhaily,Al Fiqhul Islami wa ‘Adilatuhu, Beirut: Daar al Fikr, juz 2, h. 238. 82. Ibid , h. 267. 83. Obid h. 270. 258_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 84. Joseph Schacht, Pengantar Hukum Islam, terj., Depag., 1985, h. 123. 85. Lihat juga: N.J Coulson,MA, Aljazair History of Islamic Law, Edinburgh: Edinburgh University, 1964, h. 171. 86. ahir Mahmood, Family Reform in the Muslim World, New Delhi: The Indian law Institute, 1972, h. 129. 87. Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987, h. 15. 88. Tahir Mahmood, Family Reform…, h. 129. 89. Khoiruddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara, Jakarta-Leiden: INIS, 2002, h. 278. 90. Wahbah al-Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh, jilid IX, h. 6654. 91. Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries, h. 16-17. 92. Muhammad Jawad Mughniyyah, al Ahwal al Syakhsiyyah, Beirut: Dar al ‘Ilmi lil Malayain, tt. h. 16. 93. Abdur Rahman al-jaziri, al-Fiqh ala al-Madzâhib al-Arba’ah, Solo: Toko Kitab AS, tt, juz IV, h. 52. Administrasi Perkawinan di Dunia Islam Modern _259 Administration Marriage in the Modern Islamic World Administrasi Perkawinan di Dunia Islam Modern Ahmad Tholabi Kharlie Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta email: [email protected] Abstract: Based on the demands of today, the regulation on registration of marriages started to be valid in some Muslim countries. There is only some highlight formalism aspects of an sich which has no effect on the substance at the level of criminalization which penalizing the offenders, like criminals. However, in the study of classical fiqh, the discussion about the registration of marriage can not be found in the literature. New registration appears when the world development more complex and problems of human life on the earth becoming complicated. Therefore, the positive marriage legal provisions applicable in various Muslim countries concerning the registration of marriage which is a leap of thought in the discourse of family law in the Islamic world. In the other words, there is point of departure which is not only take the development format, but more than that, the marriage registration provisions application has led munakahât to achieve ideal performance and should be appreciated. Abstraksi : Seiring dengan tuntutan perkembangan zaman, regulasi tentang pencatatan perkawinan mulai diberlakukan di negeri-negeri muslim mutakhir. Ada yang hanya sekadar menonjolkan aspek formalisme an sich tanpa berpengaruh terhadap substansi hingga pada tataran kriminalisasi yang menjatuhkan sanksi kepada para pelanggarnya, layaknya para pelaku kriminal.Meskipun demikian, dalam kajian fikih klasik, pembahasan tentang pencatatan perkawinan tidak dapat dijumpai dalam berbagai literatur. Pencatatan baru mencuat ketika perkembangan dunia kian kompleks dan problematika kehidupan umat manusia di muka bumi menjadi semakin rumit. Oleh karena itu, ketentuan hukum perkawinan positif yang berlaku di berbagai negeri 260_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 muslim menyangkut pencatatan perkawinan ini merupakan lompatan pemikiran dalam diskursus hukum keluarga di dunia Islam mutakhir. Dalam arti kata lain, telah terjadi keberanjakan (point of departure) yang tidak hanya mengambil bentuk pengembangan format, namun lebih dari itu, pemberlakuan ketentuan pencatatan perkawinan telah mengantarkan hukum munakahât mencapai performa yang ideal dan patut diapresiasi. Keywords: marriage registration, KUA, family law, Islamic world A.Pendahuluan “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (mîtsâq-an ghalîzhan).”(QS.Al-Nisâ/4: 21) Demikian Tuhan menggambarkan kukuhnya tali perkawinan (mîtsâqan ghalîzhatan). Dalam al-Qur’an, istilah serupa muncul pada tiga tempat,1 yakni surat al-Nisâ/4 ayat 21 berkenaan dengan hubungan suami-isteri (perkawinan), surat al-Nisâ’/4 ayat 154 yang berkisah tentang perjanjian Allah dengan manusia dalam konteks melaksanakan pesan-pesan agama, dan surat al-Ahzâb/33 ayat 7 tentang transaksi Tuhan dengan para Nabi-Nya. Mengamati ketiga konteks penggunaan terminologi “mîtsâq-an ghalîzhatan” melempangkan suatu persepsi tentang keluhuran obyek perikatan. Bagaimana tidak, ketika Tuhan membangun kontrak yang kuat dengan para kekasih-Nya menyangkut “misi langit” yang Mahaagung, dan pada saat yang sama Dia pun meniscayakan kesebandingan keagungannya dengan transaksi antara suami dan isteri dalam ikatan akad perkawinan. Jika akad perkawinan dianggap sebagai ikatan yang kukuh, sebagaimana kukuhnya perjanjian Tuhan dengan manusia dan para nabiNya, maka sejatinya perkawinan menjadi tidak hanya bermakna ritus Administrasi Perkawinan di Dunia Islam Modern _261 pribadi an sich, namun harus dianggap sebagai peristiwa agung lagi sakral, baik secara vertikal maupun horizontal. Maka sebagaimana layaknya suatu perhelatan (transaksi) agung al-Qur’an selalu menganjurkan agar diabadikan, seperti halnya utang piutang. Kalau toh transaksi utang-piutang (mudâyanah), yang notabene merupakan transaksi muamalat, secara khusus mendapat perhatian nashal-Qur’an dan diabadikan dalam surat al-Baqarah/2 ayat 282, maka transaksi perkawinan yang jelas-jelas jauh lebih sakral dan memiliki makna yang sangat adiluhung sejatinya mendapat perhatian yang proporsional, lebih dari sekadar transaksi jual-beli. Dalam konteks fikih munakahat klasik, pembahasan tentang pencatatan perkawinan tidak dapat dijumpai dalam berbagai literatur. Pencatatan baru mencuat ketika perkembangan dunia kian kompleks dan problematika kehidupan umat manusia di muka bumi menjadi semakin rumit. Pertanyaannya, bagaimana sesungguhnya argumentasi normatif dan celah-celah yang dapat ditembus untuk mendukung pemberlakuan pencatatan perkawinan ini? Dan seberapa jauh keberanjakan negerinegeri muslim di dunia modern dalam mengimplementasikan regulasi anyar tersebut? B.Landasan dan Argumentasi Normatif Sejauh ini syariah Islam, baik dalam al-Qur’an maupun Sunnah, tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat muamalat (mudâyanah) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Oleh karena derasnya perkembangan zaman, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan yang ada, maka tidak mengherankan jika hampir seluruh negara di dunia Islam modern menerapkan peraturan tersebut.2 Pada dasarnya, pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan dalam rangka melindungi martabat dan kesucian (mitsâqan ghalîzhatan) perkawinan, dan lebih 262_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 khusus lagi memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam kehidupan keluarga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, yang masing-masing suami-isteri mendapatkan salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masingmasing. Karena dengan akta tersebut, suami-isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.3 Pencatatan perkawinan dan aktanya, bagi sebagian masyarakat tampaknya masih perlu disosialisasikan. Boleh jadi hal ini akibat pemahaman yang fikih sentris, yang dalam kitab fikih sejauh ini hampir tidak pernah dibicarakan, sejalan dengan situasi dan kondisi waktu fikih itu ditulis. Namun, jika kita mencoba memperhatikan ayat mudâyanah (QS.Al-Baqarah/2: 282) mengisyaratkan bahwa adanya bukti otentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum. Bahkan, secara redaksional menunjukkan bahwa “pencatatan” (kitâbat) didahulukan dari pada “kesaksian”, yang dalam perkawinan (persaksian) menjadi salah satu rukun yang harus dilaksanakan.4 Mengomentari ayat mudâyanah tersebut, Syeikh Muhammad Rasyîd Ridhâ menilai bahwa, “Demikianlah keberadaan perangkat hukum dalam ayat ini jauh lebih terang dari pada (cahaya) matahari, baik dari segi maknanya, maupun dari sisi illat (alasan logis) hukum dan hikmah (dampak positif) yang terkandung di dalamnya.” 5 Seperti diketahui, kebanyakan mufassir berpendirian bahwa perintah menuliskan transaksi utang-piutang pada ayat 282 surat al-Baqarah adalah semata-mata bersifat anjuran (amr li al-nadb) berdasarkan beberapa alasan berikut ini, pertama, adanya firman Allah yang membolehkan ketiadaan penulisan akad utang-piutang, dengan alasan karena ikrar mereka (kreditur dan debitur) yang tetap mengikat meskipun tidak dilakukan secara tertulis dan atau di hadapan para saksi, dâ’in, dan mudâ’in. Administrasi Perkawinan di Dunia Islam Modern _263 Kedua, sejak di masa-masa awal Islam dan periode-periode berikutnya, kenyataan menunjukan bahwa kaum muslimin tidak pernah mewajibkan transaksi utang-piutang harus dilakukan secara tertulis atau di hadapan para saksi; mengingat praktik seperti itu kadang-kadang memang dipraktikkan, tetapi tidak jarang pula pada kesempatan lain tidak digunakan. Sekiranya pencatatan utang-piutang itu diharuskan, niscaya mereka, kaum muslimin, mewajibkan praktik pencatatan utang-piutang ini pada masanya. Tidak diindahkannya pencatatan utang-piutang oleh kaum muslimin ini, oleh sebagian ahli tafsir, khususnya al-Râzi, dijadikan dasar konsensus ulama (ijma’) tentang ketidakharusan menulis utangpiutang (mudâyanah). Ketiga, keharusan mencatat transaksi utang piutang, yang dinafikan oleh nash justru hanya akan menimbulkan kesulitan dalam memperlancar proses jalannya transaksi utang-piutang. Sebagian ulama lain, di antaranya ‘Atha’ al-Sya’bi dan Ibn Jarîr alThabarî berpendapat bahwa perintah menuliskan transaksi utangpiutang itu adalah wajib. Hal ini didasarkan pada kaidah, “Pada dasarnya, perintah itu wajib”. Dan inilah yang justru dipedomani oleh mayoritas ahli hukum Islam. Kaidah ini kemudian disertai dengan beberapa perintah yang terdapat dalam ayat ini, yang fungsinya tidak lain hanyalah sebagai penguat. Buktinya, untuk kasus orang-orang tertentu, dalam hal ini orang idiot (safah) dan lemah akal, tetap saja diperintahkan supaya mencatat yang pencatatannya diwakili oleh wali-wali mereka yang berhak. Dan mereka (orang bodoh dan idiot) itu sama sekali tidak dimaafkan (dispensasi) untuk tidak menuliskan transaksi utang-piutangnya, terbukti dengan mengharuskan walinya mendiktekan di hadapan pencatat (notaris). Penguatan ketentuan semacam ini tidak mungkin terdapat pada hal-hal yang tidak wajib.6 264_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 Pendapat kedua inilah yang kemudian dipilih oleh syaikh Muhammad ‘‘Abduh, seraya menambahkan beberapa dalil lain dalam upaya membantah argumentasi kelompok pertama. Alasan mereka yang mengatakan bahwa kewajiban mencatat transaksi utang-piutang menyulitkan kaum muslimin dibantah ‘‘Abduh, “Di mana letak kesulitannya?” Kata ‘Abduh dengan nada tanya. Kalaupun kewajiban mencatat transaski utang-piutang itu benar-benar akan menimbulkan kesulitan, maka yang akan terkena pasti hanya sebagian kecil saja dari kalangan orang-orang dewasa. Anehnya, mengapa mereka tidak merasa kesulitan dengan keharusan berwudhu yang harus dilakukan oleh setiap mukallaf setiap hari ketika hendak melaksanakan shalat lima waktu. Kalau ini tidak memberatkan mengapa pencatatan tersebut justru memberatkan, ujar ‘Abduh.7 ‘Abduh juga berpendapat bahwa yang dimaksud dengan keharusan menghilangkan kesempitan dan kesulitan oleh nash itu adalah dalam rangka menghilangkah masyaqah (kepayahan) dan meniadakan pembebanan kepada mukallaf, akan tetapi yang dimaksudkan ialah pembebanan itu sendiri bukan dimaksud memberatkan dan menimbulkan kesulitan itu sendiri bagi orang-orang mukallaf melainkan pada setiap hukum itu pasti mengandung satu atau beberapa nilai guna yang justru menghilangkan kesempitan dan kesulitan. Dan dengan ini pula, kaum muslimin diharapkan dapat meningkatkan keterampilannya, terutama keahlian tulis-baca. Demikian ‘Abduh.8 Berkenaan dengan konteks perbincangan mengenai pencatatan perkawinan, sejauh ini tidak dijumpai sumber-sumber fikih yang menyebutkan mengapa dalam hal pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah, tidak dianalogikan kepada ayat muamalat tersebut. Dalam kaidah hukum Islam, pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah, sangat jelas dapat mendatangkan maslahat bagi tegaknya mahligai rumah tangga. Hal ini sejalan dengan prinsip: النِن َالكاح ِنالَّالبِنوِن وش ِن اى َالدبِن َال ْدد ٍلل َال َال َال ّ َال َال Administrasi Perkawinan di Dunia Islam Modern _265 در املفاسد مقدم على جلب املصاحل “Menolak kemadaratan kemaslahatan” lebih didahulukan dari pada memperoleh تصرف االمام على الرعية منوط باملصلحة “Suatu tindakan (peraturan) pemerintah berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan masyarakat” Selain itu, ada pula hal menarik dalam kajian fikih klasik. Pembahasan yang relevan dan (agaknya) dapat ditarik ke dalam persoalan pencatatan perkawinan masa kini adalah regulasi tentang saksi dan pengumuman perkawinan. Indikatornya dapat dilihat dari kecenderungan ahli fikih yang menempatkan kedua tema tersebut dalam pembahasan yang mandiri.9 Kenyataan ini menimbulkan keyakinan, bahwa masalah perkawinan memang erat kaitannya dengan masalah saksi dan i’lân.10 Pembahasan tentang saksi, dalam literatur fikih klasik, agaknya cukup beragam namun terkesan dinamis. Hal mana disebabkan para ulama berbeda pandangan dalam menerjemahkan regulasi saksi dalam perkawinan ini. Pembahasan tentang saksi menjadi penting ketika terdapat relevansi kuat dengan persoalan pencatatan perkawinan. Implikasinya, pandangan-pandangan fikih terhadap keberadaan saksi dalam perkawinan akan dengan mudah ditarik (hukumnya) dalam wilayah pencatatan perkawinan. Imam Abu Hanifah dan pengikutnya (Hanafiyah), misalnya, berpandangan bahwa saksi adalah salah satu rukun yang harus ada dalam setiap akad perkawinan.11 Jika tidak, maka perkawinan dianggap tidak sah. Hal ini berbeda secara diametral dengan pandangan Imam Malik bin Anas yang menitikberatkan bukan pada sosok saksinya, tetapi pada fungsi yang diemban oleh para saksi, yakni iklan atau pengumuman. Maka menurut Malik, saksi tidak termasuk dalam rukun nikah, tetapi menjadi rukun adalah pengumuman (i’lân). 266_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 Senada dengan Hanafiyah, Imam al-Syafi’i juga mengharuskan adanya saksi dalam perkawinan. Saksi dalam perkawinan haruslah dua orang pria yang adil. Bahkan, persaksian dua orang saksi bermusuhan dengan para calon mempelai dapat diterima, dan perkawinannya sah, dengan catatan tetap adil dan mengakui perkawinan tersebut. Untuk menunjukkan keharusan adanya saksi dalam perkawinan, al-Syafi’i menulis sejumlah Hadis dan Âtsâr. Di antara Hadisnya ialah riwayat Muslim dari Ibnu Abbas, yang mengharuskan saksi yang adil dan wali dewasa (mursyid), ditambah âtsâr Umar yang tidak mengakui perkawinan yang hanya dihadiri satu orang saksi pria dan satu saksi wanita. Oleh Umar, perkawinan semacam ini diketegorikan sebagai perkawinan sirri yang terlarang.12 Sementara itu Ibnu Qudâmah, salah seorang Hanabilah yang populer, berpandangan bahwa saksi dalam perkawinan harus ada.13 Saksi dalam perkawinan, menurut dia, tidak boleh seorang zimmi ataupun wanita. Tapi dia membolehkan seorang buta bersaksi, dengan syarat mengetahui benar terhadap suara orang yang tengah melakukan akad perkawinan itu, dan diperkirakan mengetahui seperti apa yang diketahui oleh orang yang tidak buta. Di samping harus ada saksi dalam akad nikah, Ibnu Qudâmah juga mengatakan bahwa disunahkan mengumumkan perkawinan sehingga orang lain mengetahuinya. Hukum mengumumkan menurut Ibnu Qudâmah hanya sunnah, berdasarkan perintah untuk mengadakan pukulan-pukulan gendang (rebana) dan suara, tetapi perintah ini bukan perintah wajib. Sekiranya pengumuman menjadi syarat akad, pasti disyaratkan seperti syaratsyarat lain.14 Dengan demikian, Ibnu Qudâmah membedakan antara saksi dan pengumuman. Saksi merupakan rukun nikah yang harus ada (wajib) ketika melakukan akad nikah, sedangkan pengumuman adalah hal lain di luar akad nikah, yang hukumnya hanya sunnah. Dari pembahasan di atas, tampak bahwa pada prinsipnya semua ulama tersebut mewajibkan adanya saksi dalam akad nikah, hanya saja Imam Malik terlihat lebih menekankan fungsi saksi, yakni sebagai Administrasi Perkawinan di Dunia Islam Modern _267 sarana pengumuman dari pada hanya sekadar hadirnya pada waktu akad nikah, seperti yang dipegang ulama lain. Akibatnya terkesan Imam Malik tidak mengharuskan saksi dalam akad nikah.15 Menarik ‘benang merah’ pandangan para fuqaha terkemuka di atas, membuka jalan tentang pemahaman bahwa, agaknya, persaksian menjadi hal yang sangat penting, dan oleh karenanya diharuskan. Dan, ini paralel dengan urgensi regulasi pencatatan perkawinan yang mengandung fungsi dan kemanfaatan yang serupa. Demikian perspektif fikih klasik. Dalam perspektif hukum positif, kebijakan pemerintah yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dan dibuktikannya dengan akta nikah – meminjamistilah teknis dalam epistemologi hukum Islam—refleksi dari teori istislahatau maslahat mursalat. Hal ini karena meski secara formal tidak ada ketentuan ayat atau Sunnah yang memerintahkan pencatatan dalam urusan perkawinan, namun kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syarak yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Atau dengan memperhatikan ayat tersebut di atas, dapat dilakukan analogi (qiyas), karena terdapat kesamaan illat, yakni dampak negatif yang ditimbulkannya.16 Selain nashal-Qur’an surat al-Baqarah/2 ayat (282) yang mengindikasikan urgensi pencatatan dalam perkawinan, dalam beberapa kitab Hadis disebutkan tentang larangan orang menikah dengan sembunyi-sembunyi (ilegal), seperti, “Janganlah kalian melacur dan melakukan pernikahan sirri.”17 Hadis ini menujukkan tentang kemestian melakukan publikasi terhadap peristiwa suci tersebut. Karena pada hakikatnya, perkawinan adalah hal mulia yang patut diiklankan.18 Dalam konteks perbincangan ini, dijumpai sebuah pernyataan Sahabat Umar bin Khattab yang tidak mengakui keabsahan suatu perkawinan yang dihadiri oleh satu orang saksi saja.19Âtsâr ini menunjukkan bahwa perkawinan adalah peristiwa penting dan sakral secara privacy sekaligus membutuhkan pengakuan publik, karena pada gilirannya nanti akan bersinggungan dengan persoalan-persoalan publik. 268_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 Memang, perkawinan sejatinya merupakan transaksi yang teramat penting, bahkan jauh lebih penting ketimbang transaksi-transaksi lainnya dalam kehidupan manusia. Jika suatu transaksi muamalat (mudâyanah) harus dicatat, bukankah transaksi perkawinan merupakan hal yang lebih krusial untuk dicatatkan? Mengapa pencatatan perlu? Meski secara agama atau adat istiadat perkawinan yang tidak dicatatkan adalah sah, namun di mata hukum penguasa (hukm al-hâkim) tidak memiliki kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak tercatatkan berdampak sangat merugikan bagi isteri, dan perempuan pada umumnya. Bagi isteri, dampak hukumnya adalah tidak dianggap sebagai isteri yang sah karena tidak memiliki Akta Nikah sebagai bukti hukum yang otentik. Akibat lanjutannya, isteri tidak berhak atas nafkah dan harta warisan suami jika ia meninggal dunia dan isteri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.20 Adapun dampak bagi anak adalah status anak yang dilahirkan dianggap sebagai “anak tidak sah”. Di dalam akta kelahirannya akan dicantumkan status “anak di luar nikah”. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Tentu saja, pencantuman “anak luar nikah” akan berdampak buruk secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Selain itu, ketidakjelasan status anak di muka hukum mengakibatkan anak tidak berhak atas nafkah, warisan, biaya hidup, dan pendidikan dari ayahnya. Selain berdampak hukum, perkawinan di “bawah tangan” juga membawa dampak sosial bagi perempuan. Hal mana, perempuan yang melakukannya akan sulit bersosialisasi di tengah masyarakat karena sering dianggap sebagai isteri simpanan atau dianggap “kumpul Kebo”.21 Berdasarkan landasan dan argumentasi normatif di atas, dapat ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Karena ia memiliki Administrasi Perkawinan di Dunia Islam Modern _269 landasan metodologis yang cukup kokoh, yakni al-qiyâs dan al-maslahat al-mursalat,22 yang bahkan (maslahat) dalam pandangan al-Syâthibi dianggap sebagai dalil qath’i yang dibangun atas dasar kajian induktif (istiqra’i). C.Peraturan Perundang-undangan Seiring dengan tuntutan perkembangan zaman, regulasi tentang pencatatan perkawinan mulai diberlakukan di negeri-negeri muslim mutakhir. Ada yang hanya sekadar menonjolkan aspek formalisme an sich tanpa berbengaruh terhadap substansi hingga pada tataran kriminalisasi yang menjatuhkan sanksi kepada para pelanggarnya, layaknya para pelaku kriminal. Berikut akan dikemukakan beberapa model perundang-undangan di negeri-negeri muslim yang mengatur masalah pencatatan perkawinan. Di Indonesia23, ketentuan yang mengatur pencatatan perkawinan— yang merupakan aspek menonjol dan cukup banyak diperdebatkan keberadaannya—terdapat dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1/1974 tentang Perkawinan (UUP), pasal 2-9 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9/1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No. 1/1974, dan pasal 5-6 dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/1991 tentang Komplasi Hukum Islam (KHI). Pasal 2 ayat (2) UUP menyatakan bahwa, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”24 Dalam kaitan ini, pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI menegaskan:25 (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undangundang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954. 270_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 Adapun teknis pelaksanaannya dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) KHI sebagai berikut:26 (1) Untuk memenuhi kektentuan di dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Adapun tujuan pencatatan ini disebutkan dalam penjelasan UUP No. 4 Poin (b) paragraf II, “Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.”27 Dari Ketentuan-ketentuan di atas dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif. Jadi, tujuan pencatatan perkawinan itu tidak lain semata-mata untuk kepentingan administrasi dan tidak ada hubungannya dengan persoalan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dalam arti kata lain, tanpa pencatatan, perkawinan tetap sah, karena ukuran sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh normanorma agama dari para pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur, karena tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum karena tidak memiliki buktibukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang telah dilangsungkan. Tentu saja, kondisi demikian bertentangan dengan misi dan tujuan yang terkandung dalam perkawinan itu sendiri. Lebih lanjut, pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9/1975 mengatur Pegawai Pencatat Nikah sebagai pihak yang berhak melakukan pencatatan:28 (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan Administrasi Perkawinan di Dunia Islam Modern _271 perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Jika diperhatikan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam PP No. 9/1975 itu, yaitu tentang peraturan pelaksanaan perkawinan terdapat beberapa tahap dalam proses pencatatan perkawinan, yakni pemberitahuan, penelitian, pengumuman, dan pencatatan. 1. Pemberitahuan Perkawinan Mengenai pemberitahuan perkawinan ini diuraikan dalam dalam pasal 3-5 PP No. 9/1975. Pada pasal 3 dikemukakan:29 setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. (1) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurangkurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. (2) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah. Lebih lanjut pasal 4 PP No. 9/1975 menyebutkan bahwa, “Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.” Mengenai pasal ini dijelaskan dalam penjelasan atas PP No. 9/1975, sebagai berikut,30 “Pada prinsipnya, kehendak untuk melangsungkan perkawinan 272_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 harus dilakukan secara lisan oleh salah satu atau kedua calon mempelai, atau oleh orang tuanya atau wakilnya. Tetapi apabila karena sesuatu alasan yang sah pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan secara lisan itu tidak mungkin dilakukan, maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis. Selain itu maka dapat mewakili calon mempelai untuk memberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan adalah wali atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan kuasa hukum.” Jadi, jelaslah bahwa pemberitahuan itu pada dasarnya harus dilakukan secara lisan, dan karena sesuatu hal pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis. Selanjutnya, pasal 5 memuat apa saja yang harus diberitahukan,31 “Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu.” Dalam penjelasan atas pasal ini dikemukakan,32 “Bagi mereka yang memiliki nama kecil dan nama keluarga, maka dalam pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, dicantumkan baik nama kecil maupun nama keluarga. Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki nama keluarga, maka cukup mencantumkan nama kecilnya saja ataupun namanya saja. Tidak adanya nama kecil atau nama keluarga sekali-kali tidak dapat dijadikan alasan untuk penolakan berlangsungnya perkawinan. Hal-hal yang harus dimuat dalam pemberitaan tersebut merupakan ketentuan minimal, sehingga masih dimungkinkan ditambahkannya hal-hal lain, misalnya mengenai wali nikah, bagi mereka yang beragama Islam.” 2. Penelitian Mengenai penelitian ini diatur dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9/1975: Administrasi Perkawinan di Dunia Islam Modern _273 (1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang. Lebih lanjut ayat (2) mengemukakan hal-hal lain yang diteliti, yakni: kutipan akta kelahiran, keterangan mengenai nama, agama, pekerjaan, izin tertulis pengadilan mengenai dispensasi umur dan poligami, dan lain-lain. Penelitian tersebut kemudian ditulis dalam sebuah daftar yang telah disediakan (pasal 7 ayat/1 dan/2). 3. Pengumuman Jika segala persyaratan tentang pemberitahuan telah terpenuhi serta hasil penelitian menunjukkan tidak terdapatnya halangan permanen, maka Petugas Pencatat Nikah menyelenggarakan pengumuman dengan cara menempelkan surat pengumuman memuat formulir yang ditentukan untuk maksud tersebut pada tempat yang telah ditentukan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 8 PP No. 9/1975 sebagai berikut,33 “Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan. Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.” Adapun yang dimuat dalam formulir pengumuman tersebut dikemukakan dalam pasal 9:34 (1) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu; (2) Hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan akan dilangsungkan. 274_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 4. Pencatatan Yang dimaksud dengan pencatatan di sini adalah pencatatan dalam pengertian sempit, yaitu sesuai dengan ayat (3) pasal 11 PP No.9/1975. perkawinan dicatat secara resmi jika akta perkawinan itu telah ditandatangani oleh kedua mempelai, dua orang saksi, Petugas Pencatat Nikah (PPN), dan wali. Selain itu pihak-pihak tersebut harus pula menandatangani buku daftar perkawinan. Demikianlah beberapa landasan yuridis yang mengatur pencatatan perkawinan di Indonesia. Sejauh ini, secara normatif, diktum mengenai pencatatan perkawinan di Indonesia dalam pandangan ahli hukum sama sekali tidak terkait dengan persoalan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Meskipun demikian, tak urung, perdebatan publik mengenai keberadaan pasal yang pencatatan ini cukup hangat mengemuka.35 Sebagaimana halnya di Indonesia, hukum perkawinan negara Malaysia36 juga mengharuskan adanya pendaftaran atau pencatatan perkawinan. Di antara undang-undang yang mengatur (di samping berbagai perundangan yang sama berdasarkan wilayah) adalah Undangundang Pinang tahun 1985 pasal 25 yang berbunyi:37 “Perkawinan selepas tarikh yang ditetapkan tiap-tiap orang yang bermastautin dalam Negeri Pulau Pinang dan perkawinan tiap-tiap orang yang tinggal di luar negeri tetapi bermastautin dalam Negeri Pulau Pinang hendaklah didaftarkan mengikuti Enakmen ini.” Secara prinsipil, proses pencatatan perkawinan dilakukan setelah selesai akad nikah. Hanya saja dalam tahap operasionalnya proses pencatatan ada tiga jenis. (1) untuk orang-orang yang tinggal di negara masing-masing pencatatan dilakukan segera setelah akad, kecuali Kelantan yang menetapkan 7 hari setelah akad nikah; (2) orang asli Malaysia yang menikah di kedutaan Malaysia di luar negeri sama dengan yang tinggal di negeri sendiri. Perbedaannya terletak pada petugas yang melakukan pencatatan; (3) orang Malaysia yang menikah di luar negeri tapi bukan di kedutaannya, maka rentang waktu pendaftaran Administrasi Perkawinan di Dunia Islam Modern _275 adalah enam bulan pasca akad kepada petugas yang ditunjuk kedutaan. Jika pulang ke Malaysia masih dalam tenggang waktu tersebut dapat mendaftar di Malaysia. Jika dicermati, peraturan yang mengharuskan pencatatan perkawinan di Malaysia berfungsi sebagai syarat administrasi, dan tidak ada kaitannya dengan sah atau tidaknya akad nikah. Negara Brunei Darussalam38 juga mengharuskan adanya pendaftaran (pencatatan) perkawinan, meskipun dilakukan setelah dilangsungkannya akad nikah. Dan lewat pendaftaran inilah Pegawai Pendaftar memeriksa kelengkapan administrasi pendaftaran. Hal ini diatur dalam Religious Council and Kadis Courts pasal 143 ayat (1) dan (2):39 (1) Dalam jangka waktu 7 hari setelah melakukan akad nikah para pihak diharuskan melapor perkawinan tersebut, yang boleh jadi para pasangan atau wali. (2) Pencatat wajib memeriksa apakah seluruh persyaratan perkawinan sudah terpenuhi sebelum melakukan pencatatan. Selanjutnya, bagi pihak-pihak yang tidak mendaftarkan perkawinannya, maka dapat dikenakan sanksi kurungan atau denda. Ketentuan ini diatur dalam pada pasal 180 ayat (1), “Seorang yang seharusnya tapi tidak melaporkan perkawinan atau perceraian kepada Pegawai Pencatat adalah satu pelanggaran yang dapat mengakibatkan dihukum dengan hukuman penjara atau denda $ 200.” Sebagaimana halnya Brunei, Singapura40 menerapkan ketentuan yang mengharuskan pencatatan perkawinan (pasal 102) dan menganggap tindak melanggar hukum bagi mereka yang tidak mau mencatatkannya (pasal 130) dan diancam dengan hukuman denda $ 500. Demikian juga bagi para pihak atau petugas yang melanggar ketentuan ini dapat dikenakan sanksi yang sama atau penjara 6 bulan (pasal 133). Pasal 81 Code of Muslim Personal Laws of The Philippines Tahun 1977 mengharuskan warga Filipina41 untuk mencatatkan perkawinan mereka 276_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 yang fungsinya sebagai data administrasi. Tetapi sejauh ini tidak dijelaskan tentang status dan akibat hukum bagi perkawinan yang tidak dicatatkan. Dalam undang-undang Lebanon42(The Law of The Right of The Family of 16 July 1962) hanya disebutkan, seharusnya pegawai yang berwenang hadir dan mencatatkan perkawinan (akad nikah). Sebaliknya, tidak ada penjelasan tentang status dan akibat hukum perkawinan yang tidak sesuai dengan prosedur ini.43 Sementara itu, masalah pencatatan perkawinan di negara Pakistan44 merupakan salah satu ketentuan yang sangat penting dalam pelaksanaan perkawinan, sebagaimana halnya di Indonesia. Pemerintah Pakistan mewajibkan setiap perkawinan untuk dicatatkan. Ketentuan mengenai wajibnya pencatatan perkawinan ini termuat dalam Ordonansi Hukum Keluarga Islam Tahun 1961 (The Muslim Family Laws Ordonance, 1961) seksi 5 ayat (1),45 “Every marriage solemnized under Muslim law shall be registered in accordance with the provisions of this ordinance.” “Setiap pekawinan dalam lingkup hukum Islam harus dicatatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku”. Selanjutnya dalam seksi 5 ayat (2) dinyatakan,46 “For the purpose of registrsation of marriage under this ordinance, The Union Council shall grant licences to one or more persons, to be called Nikâh Registrars, but in no case shall more than one Nikâh Registrar be licensed for any one ward.” “Untuk tujuan pencatatan perkawinan menurut ordonansi ini, Majelis Keluarga (The Union Council) akan memberikan surat izin kepada seseorang atau beberapa orang, yang disebut sebagai Pegawai Pencatat Nikah (Nikâh Registrar), tetapi dalam suatu kasus tidak diizinkan lebih dari satu orang Pencatat Nikah untuk satu daerah tertentu.” Administrasi Perkawinan di Dunia Islam Modern _277 Berdasarkan ketentuan di atas, Majelis Keluargalah yang berhak mencatat Pegawai Pencatat Nikah yang akan melakukan pencatatan akad nikah, dan majelis itu memberikan izin untuk melakukan pekerjaan tersebut hanya kepada satu orang saja pada setiap daerah tertentu. Pada ayat (3), dijelaskan bahwa setiap perkawinan yang tidak dilaksanakan oleh Petugas Pencatat Nikah harus dilaporkan kepada pegawai tersebut oleh orang yang melangsungkan perkawinan tersebut. Jika hal ini tidak dilakukan, maka dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (pelanggaran). Dengan demikian, tugas utama Pegawai Pencatat Nikah adalah mencatat masalah-masalah administratif yang berkaitan dengan akad nikah, dan dia dapat saja tidak hadir pada saat pelaksanaan akad nikah tersebut. Lebih jelas dapat dikemukakan seksi 5 ayat (3) dimaksud,47 “Every marriage not solemnized by the Nikah Registrar shall, for the purpose of registration under this ordinance, be reported to him by the person who has solemnized such marriage.” “Setiap perkawinan yang tidak dihadiri oleh Petugas Pencatat Nikah, yang dimaksudkan untuk dicatatkan berdasarkan ordonansi ini, maka yang bersangkutan harus melaporkan peristiwa tersebut kepada petugas.” Dalam seksi ini juga dijelaskan, bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan tidaklah dianggap batal, tetap sah. Hanya saja, pihak-pihak yang berakad dan saksi-saksi yang melanggar ketentuan tersebut mendapat sanksi karena tidak mencatatkan perkawinan tersebut. Secara tegas pelanggaran terhadap ketentuan tersebut tertera dalam ayat (4) seksi 5,48 “Whoever contravenes the provisions of subsection (3) shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine wich may extend to one thousand rupees, or with both.” “Barangsiapa yang tidak mengindahkan ketentuan dalam ayat (3) 278_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 akan dihukum dengan kurungan penjara ringan paling lama tiga bulan, atau denda setinggi-tingginya seribu rupee, atau dengan kedua-duanya.” Ketentuan hukum—dengan memberikan sanksi—seperti itu sama sekali tidak bertentangan dengan asas-asas pemikiran pidana Islam yang justeru memberi hak kepada penguasa untuk memberikan takzir bila diperlukan guna mempertahankan kepentingan-kepentingan yang dikehendaki oleh Syarak. Di negara Yordania49, ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-undang Tahun 1976 pasal 17. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa mempelai pria berkewajiban untuk mendatangkan qâdhi atau wakilnya dalam upacara perkawinan.50 Petugas yang berwenang, sebagaimana yang ditunjuk oleh qâdhi, mencatat perkawinan tersebut dan mengeluarkan sertifikat perkawinan. Apabila perkawinan dilangsungkan tanpa pencatatan, maka orang yang mengadakan upacara perkawinan (kedua mempelai) dan saksi-saksi dapat dikenakan hukuman berdasarkan “Jordanian Penal Code” dan denda lebih dari 100 dinar.51 Sementara itu di Mesir52, persoalan pencatatan tidak dikemukakan secara jelas dalam beberapa literatur. Seperti diketahui bahwa negara ini telah melakukan beberapa amandemen. Ada beberapa hal yang dapat dikemukakan menyangkut hasil amandemen UU Nomor 100 tahun 1985. dalam amandemen ini dinyatakan bahwa seorang yang akan menikah harus menjelaskan status perkawinan pada formulir pencatatan perkawinan. Bagi yang sudah beristri, harus mencantumkan nama dan alamat isteri atau isteri-isterinya. Pegawai pencatat harus memberitahukan istrinya tentang rencana tersebut. Seorang istri yang suaminya menikah lagi dengan wanita lain, dapat diminta cerai berdasarkan kemudaratan ekonomi yang diakibatkan poligami dan mengakibatkan tidak mungkin hidup bersama dengan suaminya. Hak cerai ini dapat berlaku, baik ditetapkan ataupun tidak, dalam taklik talak. Jika hakim tidak dapat mendamaikan, maka perceraianlah yang terjadi. Hak isteri minta cerai Administrasi Perkawinan di Dunia Islam Modern _279 hilang dengan sendirinya kalau ia tidak memintanya selama masa satu tahun setelah dia mengetahui perkawinan tersebut.53 Di samping itu, hukum keluarga Mesir juga memberitakan ancaman kepada orang yang memberikan pengakuan palsu kepada pegawai pencatat tentang status perkawinan atau alamat isteri atau isteri-isterinya, atau isteri yang dicerai. Seorang pegawai pencatat yang lalai atau gagal melaksanakan tugasnya dapat dihukum dengan hukuman penjara maksimal 1 bulan dan hukuman denda maksimal 50 Pound Mesir, dan pegawai yang bersangkutan dinonaktifkan maksimal selama 1 tahun.54 Mencermati beberapa hal di atas, tampak bahwa persoalan pencatatan perkawinan di Mesir menjadi bagian penting. Hal ini dapat diamati dari keberadaan Petugas Pencatat Nikah dan tingkat partisipasi mereka dalam persoalan administrasi perkawinan. Di negara Libya55, ketentuan yang menunjuk adanya keharusan pencatatan perkawinan terdapat dalam pasal 5 Hukum Nomor 10 Tahun 1984 hal mana secara khusus berkaitan langsung dengan persoalan perkawinan, perceraian, dan konsekuensi yang menyertainya,56 “Marriage shall be proved by an official document or by a ruling of the court.” “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan dokumen resmi pemerintah atau pengadilan.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa perkawinan dianggap absah jika mendapat legitimasi dari pihak-pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah dan badan peradilan. Dalam arti kata lain, perkawinan yang bersifat ilegal (sirri) dan, tentu saja, tidak terdaftar di kantor pemerintahan dianggap tidak sah. Namun sejauh ini, selain sanksi administrasi, tidak dijumpai mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap mereka yang melakukan perkawinan ilegal. Pasal 14 Undang-undang Republik Yaman57 No. 20 Tahun 1992 mengharuskan pencatatn perkawinan. Mereka yang tidak mancatatkannya, paling lambat 7 hari setelah dilangsungkannya akad nikah, dapat diancam dengan sanksi penjara. 280_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 Aljazair58 hanya menetapkan, bahwa akad nikah boleh dilakukan setelah mendapat pengesahan dari pegawai yang berwenang. Ketentuan ini diatur dalam UU Aljazair No. 84-11 tahun 1984 pasal 18. Sebaliknya, tidak ada aturan atau penjelasan tentang status pencatatan perkawinan. Tunisia59 menetapkan, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan catatan resmi dari pemerintah (official document) sesuai dengan UU Tunisia No. 40 Tahun 1957, yang telah diperbarui tahun 1962, 1964, 1966, dan 1981, pasal 4. Maroko60 malah mensyaratkan tanda tangan dua notaris untuk absahnya suatu perkawinan. Selanjutnya, catatan asli harus dibawa ke pengadilan, dan salinannya dikirim ke Direktoral Pencatatan Sipil. Demikian halnya istri mendapat catatan asli dan salinan bagi suami, selama maksimal 15 hari dari akad nikah. Hal ini diatur dalam The Code of Personal Status Tahun 1957/1958, pasal 42 ayat (6). Aturan menarik dapat ditemukan dalam UU Syiria61 No. 34 Tahun 1975 pasal 40 ayat (1), yang menetapkan formulir perkawinan harus disampaikan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan, yang salah satu aspek dari formulir tersebut adalah keterangan dari dokter bahwa yang bersangkutan tidak sedang mengidap penyakit menular. Selanjutnya, perkawinan harus dilakukan di pengadilan, meskpiun dimungkinkan terjadinya perkawinan di luar pengadilan. Selaras dengan Syiria, UU Irak (pasal 11 ayat/1, di samping mengharuskan pencatatan, dalam catatan juga harus dilampirkan surat keterangan dokter bahwa yang bersangkutan tidak sedang mengidap penyakit menular. Bersamaan dengan itu, sanksi bagi yang melanggar aturan pencatatan dibedakan antara yang sudah pernah menikah dengan yang belum. Yakni minimal 6 bulan dan maksimal 1 tahun penjara atau denda minimal 300 dinar dan maksimal 1000 dinar bagi yang belum pernah menikah. Serta minimal 3 tahun dan maksimal 5 tahun penjara bagi yang sudah menikah. Administrasi Perkawinan di Dunia Islam Modern _281 Dengan demikian, secara umum undang-undang perkawinan muslim kontemporer mengharuskan pencatatan perkawinan, kecuali Aljazair yang tidak mencantumkan aturan tentang pencatatan perkawinan. Hanya saja dalam rincian keharusan pencatatan perkawinan tersebut ditemukan keragaman aturan, dan dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok besar.62Pertama, kelompok yang menetapkan pencatatan sebagai satu keharusan, dan menghukum pihak-pihak yang melanggar, atau perkawinan yang dilakukan tidak memiliki kekuatan hukum. Yang termasuk kelompok ini adalah Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Mesir, Iran, India, Pakistan, Yordania, Tunisia, Irak, dan Republik Yaman. Kedua, kelompok yang menjadikan pencatatan sebagai syarat administrasi, tetapi tidak menegaskan status dan akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan. Yang termasuk kelompok ini adalah Filipina, Lebanon, Maroko, dan Libya. Ketiga, kelompok yang meskipun mengharuskan pencatatan tapi masih mengakui perkawinan yang tidak dicatatkan. Dalam hal ini hanya Syiria yang masuk dalam kategori ini. Namun demikian, meskipun telah melakukan upaya agar pencatatan menjadi syarat sah perkawinan, kelompok pembaru belum mampu menghadapi kelompok tradisionalis yang menolak upaya tersebut. Maka dengan demikian, tidak satupun negara muslim yang menjadikan pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan. D.Penutup Ketentuan hukum perkawinan positif yang berlaku di berbagai negeri muslim menyangkut pencatatan perkawinan merupakan lompatan pemikiran dalam diskursus hukum keluarga di dunia Islam mutakhir. Dalam arti kata lain, telah terjadi keberanjakan (departure) yang tidak hanya mengambil bentuk pengembangan format, namun lebih dari itu, 282_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 pemberlakuan ketentuan pencatatan perkawinan telah mengantarkan hukum munakahat mencapai performa yang ideal dan patut diapresiasi. Namun demikian, problematika internal yang kini dihadapi adalah, munculnya reaksi dari kalangan muslim tradisionalis yang masih kukuh dengan tradisi pemikiran fikih klasik. Keadaan ini berakibat munculnya kesan keraguan dalam perundang-undangan. Di Indonesia, misalnya, menyangkut keabsahan perkawinan, yang diatur dalam UUP, dianggap oleh para ahli hukum mengandung dualisme. Di satu sisi, perkawinan sah berdasarkan ketentuan agama dan kepercayaannya. Namun, interpretasi ini terbantahkan dengan adanya diktum yang meniscayakan keabsahan perkawinan harus dicatatkan. Menurut penulis, dualisme semacam itu bisa saja terjadi terhadap negara-negarayang mengesankan ketidaktegasan dalam mengimplementasikan ketentuan ini. Ketidaktegasan yang dimaksud adalah memposisikan ketentuan administratif tersebut sebagai bagian yang menentukan keabsahan suatu perkawinan. Dan, meskipun masih terkesan kurang mantap, Pakistan sudah menunjukkan hal yang patut dihargai. Dengan memberikan sanksi pidana terhadap mereka yang enggan melakukan pencatatan perkawinan, diharapkan membawa efek jera (detterent effect) terhadap para pelanggar. Namun demikian, melihat problematika sosial yang muncul akibat ketidaktegasan ketentuan ini, menimbulkan persoalan-persoalan baru yang lebih memusingkan banyak pihak, di antaranya: maraknya praktik-praktik poligami dan hampir semuanya ilegal (tidak tercatat), maraknya perkawinan bawah tangan (sirri) dan nikah kontrak, semakin menjamurnya prostitusi terselubung, ketiadaan akta nikah menyebabkan terabaikannya hak-hak isteri dan anak, serta ketidakjelasan status hukum mereka, ketiadaan akta nikah akan menyulitkan pengadaan akta kelahiran, dan masih banyak lagi problem sosial yang muncul. Mencermati kenyataan tersebut, maka perlu direkomendasikan halhal berikut: pertama, sejatinya aspek pencatatan dalam perkawinan Administrasi Perkawinan di Dunia Islam Modern _283 semakin dipertegas dalam diktum keabsahan perkawinan, dan, kalau perlu disertai sanksi yang memberatkan bagi pihak-pihak yang melakukan perkawinan tanpa dicatat. Kedua, pencatatan merupakan salah satu hak sipil warga. Maka, agar tidak menjadi sumber korupsi, perlu dicarikan prosedur administratif yang tepat dan terjamin. Ketiga, selama ini rendahnya pemahaman masyarakat tantang hukum adalah terletak pada sosialisasi yang tidak memadai. Aspek inilah yang sesungguhnya ikut menentukan sukses atau tidaknya perundangan yang berlaku. 284_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 Daftar Pustaka Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995. Alami, Daoud L. dan Doreen Hincheliffe, Islamic Marriage and Divorce Laws of Arab World, London: Kluwer Law International, 1996. Anas, bin Malik, Al-Muwaththa’, ttp: tp, tt. Bangsa dan Negara-Negara di Dunia, Jakarta: Direktorat Pelayanan Penerangan Luar Negeri Departemen Penerangan RI, 1997. Daulay, Saleh Partanoan, Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga di Dunia Islam, Makalah, Jakarta: Tidak Diterbitkan, 2003. Esposito, Jhon L., The Oxford Encyclopedia of Modern Islamic World, New York Oxford: Oxford University Press, 1991. Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, 2001. Mahmood, Tahir, Family Law Reform in The Muslim World, New Delhi: The Indian Law Institute, 1972. Mahmood, Tahir, Personal Law in Islamic Countries, New Delhi: The Indian Law Institute, 1987. Mardjono, Hartono, Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan, Bandung: Mizan, 1997. Mudzhar, Muhammad Atho, Islam and Islamic Law in Indonesia: A SocioHistorical Approach, Jakarta: Office of Religious Research and Development, and Training Ministery of Religious Affairs Republic of Indonesia, 2003. Administrasi Perkawinan di Dunia Islam Modern _285 Mulia, Siti Musdah, Pokok-Pokok Pikiran Bagi Revisi KHI, Makalah, Jakarta: Tidak Diterbitkan, 2003. Nasution, Khoiruddin, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia, Leiden-Jakarta: INIS, 2002. Qudâmah, bin Muwaffaq al-Dîn Abî Muhammad ‘Abdillâh bin Ahmad, Al-Mughnî wa al-Syarh al-Kabîr, Beirut: Dâr al-Fikr, 1984. Ridha, Muhammad Rasyid, Tafsir al-Qur’an al-Hakim, Beirut-Lubnan: Dar al-Fikr, tt. Rofiq, Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000. Sarakhsî, al Syams al-Dîn, Al-Mabsûth, Beirut: Dâr al-Ma’rifah, 1989. Shihab, Muhammad Quraish, Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, Jakarta: Lentera Hati, 2000. Sjadzali, Munawir, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, Jakarta: UI Press, 1990. Suma, Muhammad Amin, Pengantar Tafsir Ahkam, Jakarta: Rajawali Pers, 2001. Syâfi’i, al Muhammad bin Idrîs, Al-Umm, ttp: tp, tt. Tanûkhi, al Al-Imâm Muhammad Sahnûn bin Sa‘îd, Al-Mudawwanat alKubrâ, Beirut: Dar al-Shadir, 1323 H. 286_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 Endnotes 1. Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, Jakarta: Lentera Hati, 2000, vol. 2, cet. I,h. 368. 2. Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, h. 107. 3. Ibid,h. 108. 4. Ibid, h. 118. 5. Muhammad Rasyid Ridha, Tafsîr al-Qur’ân al-Hakîm, Beirut-Lubnan: Dar alFikr, tt, juz III, h. 117—132. 6. Muhammad Amin Suma, Pengantar Tafsir Ahkam, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, h. 161. 7. Ibid. 8. Ibid. 9. Dapat diambil contoh, apa yang dilakukan Al-Imâm Muhammad Sahnûn bin Sa‘îd al-Tanûkhi. Dia membahas secara khusus tentang perkawinan sirri (diam-diam) dan saksi dalam Al-Mudawwanat al-Kubrâ, Beirut: Dar alShadir, 1323 H. 10. Khoiruddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia,Leiden-Jakarta: INIS, 2002, h. 139. 11. Syams al-Dîn al-Sarakhsî, Al-Mabsûth,, Beirut: Dâr al-Ma’rifah, 1989, V, h. 30. 12. Muhammad bin Idrîs al-Syâfi’i, Al-Umm, TTP: TP, TT., V, h. 19. 13. Muwaffaq al-Dîn Abî Muhammad ‘Abdillâh bin Ahmad bin Qudâmah, AlMughnî wa al-Syarh al-Kabîr, Beirut: Dâr al-Fikr, 1984, VII, h. 340. 14. Ibid, h. 435. 15. Khoiruddin Nasution, Ibid, h. 146. Administrasi Perkawinan di Dunia Islam Modern _287 16. Ahmad Rofiq, Ibid, h. 121. 17. Periksa dalam Sunan al-Tirmidzi, Kitab al-Nikah, hadis no. 1008, Sunan alNasai, Kitab al-Nikah, hadis no. 3316—17, Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Nikah, hadis no. 1186. 18. Perhatikan hadis-hadis, yang mengimbau agar mengiklankan perkawinan, dalam Sunan al-Tirmidzi hadis no. 1009, Sunan Ibnu majah hadis no. 1885, dan Musnad Ahmad hadis no. 15545, dan hadis-hadis yang menghendaki hadirnya empat unsur dalam akad nikah demi sahnya suatu akad nikah. Misalnya ada Hadis yang menyatakan, اعلنوا النكاح ولو بالدف 19. Lihat dalam Malik bin Anas, Al-Muwaththa’, Kitab al-Nikah, hadis no. 982. 20. Siti Musdah Mulia, “Pokok-Pokok Pikiran Bagi Revisi KHI”, Makalah tidak Diterbitkan, 2003, h. 3. 21. Ibid. 22. Penggunaan dalil hukum lebih dari satu—seperti dalam kasus di atas— adalah logis dan masuk akal. Karena semakin banyak landasan dan argumentasi (dalil) hukum yang digunakan, maka apa yang kita pertahankan menjadi kian tak terbantahkan. 23. Secara geografis Indonesia terletak di bagian tenggara benua Asia. Meskipun jumlah penduduknya (203.583.886 jiwa [data 1996]) mayoritas beragama Islam (87%), namun secara politis Indonesia tidak menerapkan sistem pemerintahan berdasarkan syariat Islam. Dengan luas wilayah 5.193.250 km2 terdiri dari pelbagai suku, bahasa, budaya, dan agama yang sangat beragam. Umat Islam di Indonesia sebagian besar menganut mazhab Syafii. Pengaruh mazhab fikih tersebut begitu kuat mempengaruhi sikap-sikap keberagamaan masyarakatnya. Lihat dalam Bangsa dan Negara-Negara di Dunia, Jakarta: Direktorat Ppelayanan Penerangan Luar Negeri Departemen Penerangan RI, 1997, h. 113—116. 24. Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama,, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, 288_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 2001, cet. I, h. 132. 25. Ibid, h. 319 atau lihat dalam Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995, cet. II, h. 114. 26. Ibid. 27. Ibid, h. 150. 28. Ibid, h. 159. 29. Ibid,h. 159—160. 30. Ibid, h. 175. 31. Ibid,h. 160 32. Ibid,h. 174 33. Ibid,h. 161. 34. Ibid. 35. Baca gagasan dan kritik beberapa pasal krusial UUP dalam Hartono Mardjono, Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan,Bandung: Mizan, 1997. 36. Terletak di kawasan Asia Tenggara. Negara ini menganut sistem kerajaan, dengan luas wilayah 329.750 km2 dan jumlah penduduk sebanyak 19.723.587 jiwa. Lihat dalam Bangsa dan Negara-negara di Dunia, Ibid, h. 201-204. 37. Khoiruddin Nasution, Ibid, h. 150. 38. Terletak di bagian utara pulau Kalimantan. Negara dengan jumlah penduduk sekitar 292.266 (1995) dan luas wilayah hanya 5.770 km2 ini menganut sistem kerajaan. Mayoritas penduduknya menganut agama Islam (63%), disusul Budha (14%), dan Kristen (8%). Lihat dalam Bangsa dan Negara-negara di Dunia, Ibid, h. 49—50. 39. Tahir Mahmood, Family Law Reform in Thge Muslim World (New Delhi: The Indian Law Institute, 1972, h. 207. 40. Terletak kawasan Asia Tenggara dengan luas wilayah hanya 581 km2 Administrasi Perkawinan di Dunia Islam Modern _289 dan jumlah penduduk 2.890.468 jiwa. Di negara yang menganut sistem pemerintahan republik ini agama yang dominan adalah Budha (29%), Kristen (19%), Islam (16%) dan Tao (13%). Lihat dalam Bangsa dan Negaranegara di Dunia, Ibid, h. 293—294. 41. Terletak kawasan Asia Tenggara dengan luas wilayah 300.000 km2 dan jumlah penduduk 73.265.584 jiwa. Di negara yang menganut sistem pemerintahan republik ini agama yang dominan adalah Katolik Roma (83%), Kristen Protestan (9%), Islam (5%), dan animisme. Lihat dalam Bangsa dan Negara-negara di Dunia, Ibid, h. 81—84. 42. Terletak di Asia Barat Daya (kawasan Timur Tengah). Negara dengan jumlah penduduk sekitar 3.695.921 jiwa (1995) dan luas wilayah hanya 10.400 km2 ini menganut sistem republik. Mayoritas penduduknya menganut agama Islam (95%), disusul Kristen (30%). Lihat dalam Bangsa dan Negara-negara di Dunia, Ibid, h. 184—187. 43. Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries, New Delhi: The Indian Law Institute, 1987, h. 98. 44. Negara yang berbentuk Republik Islam (Islamic Republic of Pakistan) terletak dibagian selatan Asia. Di sebelah barat berbatasan dengan Iran, timur dengan India, utara berbatasan dengan Afganistan dan Cina. Luas wilayah negeri ini 803.943 km2 dengan jumlah penduduk 131.541.920 jiwa (data 1995). Yang beragama Islam berjumlah 97% terdiri dari muslim berhaluan Sunni sebanyak 77% dan Syiah sebanyak 20%. Lihat dalam Bangsa dan Negara-negara di Dunia, Ibid, h. 250. Republik Islam Pakistan adalah negara yang didirikan pada tahun 1947 dengan Islam sebagai raison d’ etre, ternyata hingga sekarang masalah tempat dan pengertian tentang Islam belum juga terselesaikan. Selisih pandangan dan benturan pendirian masih terus berlanjut antara kelompok “sekularis” dan kelompok yang ingin melaksanakan “sistem” politik, ekonomi, dan sosial Islam. Sejak kelahirannya, negara ini diwarnai dengan pergolakan politik yang selalu meledak-ledak. Kalaupun toh terjadi kompromisasi, selalu saja berjalan sesaat. 290_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 Dalam UUD 1956 nama resmi negara itu adalah Republik Islam Pakistan. Namun predikat itu sempat tertanggalkan, karena UUD 1962 menghilangkan predikat itu. Baru dikembalikan lagi setelah terjadi protes kelas dan meluas dari masyarakat. Lihat dalam Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, Jakarta: UI Press, 1990, cet. II, h. 228-232 45. Tahir Mahmood, Ibid, h. 258. 46. Ibid. 47. Ibid. 48. Ibid. 49. Yordania merupakan salah satu kerajaan yang terletak di Asia barat. Penduduknya mayoritas beragama Islam. Sebanyak 95% diantaranya beraliran Sunni dan bermazhab Hanafi. Selainnya, 4% beragama Kristen dan 1% lagi gabungan Druze dan Bahai. Lihat dalam atau amati pula dalam Bangsa dan Negara-negara di Dunia, Ibid, h. 343. Negara modern Yordania muncul kali pertama pada 1921 sebagai Emiran Transyordan. Semenjak runtuhnya Dinasti Utsmani pada 1918, Yordania berada dalam kekuasaan Inggris dan memperoleh kemerdekaannya pada 1946, yang selanjutnya menjadi kerajaan Hasyimiyah Yordania. Mayoritas penduduk Yordania pada permulaan abad ke-20 adalah petani dan pedagang yang tinggal di perdesaan. Umumnya mereka adalah penganut mazhab Hanafi. Perhatiakan Esposito, Jhon L., The Oxford Encyclopedia of Modern Islamic World, New York Oxford: Oxford University Press, 1991 Hingga tahun 1951, Yordania masih menggunakan hukum keluarga Turki Utsmani sampai diundangkannya Undang-undang Hak-hak Keluarga No. 92 tahun 1951. Undang-undang ini mengatur tentang perkawinan, perceraian, mahar, pemenuhan nafkah, dan pemeiliharaan anak. Undangundang ini, dengan demikian, sekaligus mencabut ketentuan yang terdapat pada hukum Turki Usmani. Pada perkembangan selanjutnya, Undang-undang hak-hak Keluarga tahun 1951 diganti dengan Undang-undang Status Personal Yodan 1976 yang disebut dengan “Qânûn al-Ahwâl al-Syakhshiyyah”. Undang-undang ini Administrasi Perkawinan di Dunia Islam Modern _291 didominasi oleh paham mazhab Hanafi sebagai hukum tidak tertulis yang masih tetap berlaku. Amandemen berikutnya dilakukan pada tahun 1977 yang menghasilkan Undang-undang Nomor 25 tahun 1977. Lihat dalam http://law.emory.edu /IFL/legal/jordan.htm 50. Tahir mahmood, ibid, h. 80—81. 51. Saleh Partanoan Daulay, Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga di Dunia Islam, Makalah, Jakarta: Tidak Diterbitkan, 2003, h. 19. 52. Mesir adalah negara yang terletak di Afrika Utara dengan mayoritas penduduk beragama Islam (96%). Ada beberapa kelompok minoritas religius (4%) seperti Kristen Koptik, Katolik, Protestan, dan sedikit yahudi. Sejak awal perkembangan hokum Islam, Mesir merupakan tempat kedua sekaligus pusat penyebaran mazhab Syafii. Namun belakangan, setelah menjadi bagian propinsi Dinasti Usmani, Mesir mengadopsi sistem hukum yang bersumber dari mazhab Hanfi. Lihat dalam http://www.law.emory. edu/IFL/legal/egypt.htm. 53. Daoud L. Alami dan Doreen Hincheliffe, Islamic Marriage and Divorce Laws of Arab World, London: Kluwer Law International, 1996, h. 58. 54. Ibid. Atau lihat dalam Saleh, Ibid, h. 15. 55. Republik Rakyat Sosialis Libya, Socialist People’s Libyan Arab Republik, terletak di utara benua Afrika dengan luas wilayah 1.759 km2 yang dihuni sekitar 5.248.401 jiwa (1995). Dari 97% penduduk muslim seluruhnya bermazhab Sunni dan sisanya 3% menganut agama Kristen. Lihat dalam Bangsa dan Negara-negara di Dunia, Ibid, h. 192-194. 56. Ibid, h. 182. 57. Terletak di kawasan Barat Daya Jazirah Arab. Negara dengan jumlah penduduk sekitar 14.728.474 jiwa (1995) dan luas wilayah 527.960 km2 ini menganut sistem republik. Seluruh penduduk negara ini menganut agama Islam (100%). Lihat dalam Bangsa dan Negara-negara di Dunia, Ibid, h. 342—343 292_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 58. Terletak di Afrika Barat Daya. Negara dengan jumlah penduduk sekitar 28.539.321 jiwa (1995) dan luas wilayah 2.381.741 km2 ini menganut sistem republik. Mayoritas penduduknya menganut agama Islam (99%). Lihat dalam Bangsa dan Negara-negara di Dunia, Ibid, h. 9-12. 59. Terletak di kawasan Afrika Utara. Negara dengan jumlah penduduk sekitar 8.879.845 jiwa (1995) dan luas wilayah hanya 163.610 km2 ini menganut sistem republik. Mayoritas penduduknya menganut agama Islam (98%) dan lain-lainya (2%). Lihat dalam Bangsa dan Negara-negara di Dunia, Ibid, h. 323—324. 60. Terletak di kawasan Afrika. Negara dengan jumlah penduduk sekitar 29.168.848 jiwa (1995) dan luas wilayah hanya 712.550 km2 ini menganut sistem kerajaan. Mayoritas penduduknya menganut agama Islam (99%) dan lainnya (1%). Lihat dalam Bangsa dan Negara-negara di Dunia, Ibid, h. 211—212. 61. Syiria atau Suriah terletak di Asia Barat Daya (kawasan Timur Tengah). Negara dengan jumlah penduduk sekitar 15.451. 971 jiwa (1995) dan luas wilayah 185.180 km2 ini menganut sistem republik Islam. Mayoritas penduduknya menganut agama Islam Sunni (74%), Islam golongan lain (16%), Kristen (10%).. Lihat dalam Bangsa dan Negara-negara di Dunia, Ibid, h. 309—310. 62. Khorudin Nasution, Ibid, h. 158. Implementasi Maqâshid Al-Syarî’ah dalam Putusan Bahts Al-Masâ’il _293 Implementation of Maqâshid Al-Syarî’ah in Decision of Bahts Al-Masâ’il on Interfaith Marriage Implementasi Maqâshid Al-Syarî’ah dalam Putusan Bahts Al-Masâ’il tentang Perkawinan Beda Agama Ali Mutakin Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Parung Bogor Email: [email protected] Abstract : Marriage formed tocreatea nuanced offamily in harmony, happy and prosperous(sakinah mawaddah wa Rahmah). Harmonious family, happy and prosperous marriage reflects area lization al-Usul al-khamsah or maqasidal-shari’ah. While interfaith marriage (between Muslims and non-Muslims include poly the ists and Ahlal-Kitab), isone of the emergence factors of various conflict that can be a threat of the harmony, happiness and well-being ofthe household. On the other hands, interfaith marriage also allegedly would be a threat forreligious practice (apostasy) forone of the bride and groom. Based on this, Bahtsul-Masa’il decideprohibition of the practice of any form of interfaith marriage. Abstrak : Perkawinan dibentuk untuk menciptakan keluarga yang bernuansa harmonis, bahagia dan sejahtera (sakînah mawaddah wa rahmah). Keluarga harmonis, bahagia dan sejahtera merupakan perkawinan yang mencerminkan terwujudnya alushûl al-khamsah atau maqâshid al-syarî‘ah. Sedangkan perkawinan beda agama (antara Muslim dengan non-Muslim yang mencakup Musyrik dan Ahl al-Kitâb), merupakan salah satu faktor munculnya berbagai konflik yang akan mengancam keharmonisan, kebahagiaan dan kesejahteraan rumah tangga. Di samping itu, perkawinan beda agama juga disinyalir akan mengancam praktek keagamaan (murtad) bagi salah satu kedua mempelai. Berdasarkan hal tersebut, Bahts alMasâ’il memutuskan keharaman praktek perkawinan beda agama apapun bentuknya. Keywords: Bahts al-Masâ’il, Interfaith Marriage, Maqâshid al-Syarî‘ah 294_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 A.Pendahuluan Perkawinan beda agama sebagai fakta sosial bukanlah isu baru. Para sarjana muslim di setiap zaman merespon fenomena ini dengan beragam pendapat. Walhasil, diskursus perkawinan beda agama menjadi bagian penting dalam perjalanan pemikiran Islam hingga sekarang. Berbagai fatwa dan pendapat mengemuka, dengan beragam alasan dan dasar istinbath hukum. Dalil yang sering dikedepankan adalah surat al-Baqarah/2 ayat 221 dan surat al-Mumtahanah/60 ayat 10. Para ulama sepakat bahwa wanita Muslimah tidak boleh (haram) dinikahkan dengan lelaki non-Muslim, baik dari kelompok Musyrik (penyembah berhala) maupun Ahl al-Kitâb.1 Secara historis perkawinan beda agama ini telah terjadi di kalangan umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. kemudian zaman sahabat, tabi’in hingga masa-masa berikutnya dan berlanjut sampai sekarang. Lebih-lebih dalam konteks masyarakat yang plural dan heterogen, seperti di negara Indonesia, yang merupakan bangsa multikultural dan multiagama. Pluralitas di bidang agama terwujud dalam banyaknya agama yang diakui secara sah di Indonesia, selain Islam ada agama Hindu, Budha, Kristen, Katolik, dan lain-lain.2 Sensus penduduk tahun 1980 menunjukkan bahwa Islam dipeluk oleh sebagian besar bangsa Indonesia (88,2 % dari 145 juta penduduk), disusul Protestan (5,8 %), Katolik (3%), Hindu (2,1 %), dan Budha (0,9 %). Oleh karena itu, perkawinan beda agama menjadi sebuah fakta yang wajar dan sangat mungkin terjadi.3 Bagi masyarakat Indonesia, perkawinan beda agama juga menjadi pro dan kontra. Meski bukan negara Islam, namun mayoritas penduduknya adalah muslim. Di samping itu, Indonesia juga menjadi wadah yang ramah terhadap beragam pandangan madzhab, termasuk dalam hal perkawinan beda agama. Karena itulah, pro dan kontra selalu menghiasi setiap cerita di kehidupan bermasyarakat. Implementasi Maqâshid Al-Syarî’ah dalam Putusan Bahts Al-Masâ’il _295 Fakta ini misalnya dapat dijumpai di Provinsi Yogyakarta. Berdasarkan hasil sensus perkawinan beda agama antara tahun 1990 dan 2000 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang merupakan melting pot atau wadah peleburan identitas budaya, menunjukkan bahwa di DIY terjadi fluktuasi. Pada tahun 1980, paling tidak terdapat 15 kasus perkawinan beda agama dari 1000 kasus perkawinan yang tercatat. Pada tahun 1990, naik menjadi 18 kasus dan trend-nya menurun menjadi 12 kasus pada tahun 2000. Tahun 1980 rendah (15/1000), lalu naik tahun 1990 (19/1000), kemudian turun lagi tahun 2000 (12/1000). Hasil sensus tersebut menunjukkan bahwa laki-laki cenderung melakukan perkawinan beda agama dibanding perempuan. Angka perkawinan beda agama, sesuai sensus 1980, 1990 dan 2000, paling rendah terjadi di kalangan Muslim (di bawah 1%). Hal ini menunjukan bahwa semakin besar kuantitas penduduk beragama Islam, maka pilihan kawin seagama tentu juga semakin besar. Lain halnya, bagi penganut agama yang minoritas, maka dengan sendirinya pilihan kawin dengan pasangan seagama juga semakin kecil. Dengan demikian untuk menikah beda agama, bagi penganut agama yang “minoritas,” kemungkinannya semakin besar.4 Pro dan kontra seputar perkawinan beda agama juga mendapat respon dari kalangan ormas Islam, khususnya Nahdlatul Ulama. Sebagai ormas Islam yang memiliki tradisi keilmuan yang kuat, NU telah beberapa kali mengadakan kajian tentang perkawinan beda agama ini melalui bahts al-masâ’il. Sebagai kajian akademis, bahts al-masâ’il bagi keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU) merupakan tradisi intelektual yang berkembang sejak lama, ada sebelum NU berdiri. Sebagai gambaran, tradisi diskusi di kalangan pesantren melibatkan kiyai dan santri sebelum NU berdiri. Ketika NU resmi berdiri, tradisi ini terjaga hingga kini dan menjadi wadah bagi para ulama dalam merumuskan ijtihad atas tema-tema tertentu yang actual di masyarakat. 296_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 B.Kerangka Teori 1. Konsep Maqâshid al-Syarî‘ah Tujuan syari’at atau Maqâshid al-Syarî’ah berintikan mewujudkan kemaslahatan, baik dengan cara menarik manfaat (jalb al-manâfi‘) maupun mencegah kerusakan (dar’u al-mafâsid). Kemaslahatan akan terwujud jika lima unsur pokok (ushûl al-khamsah) dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok tersebut adalah al-dîn (agama), al-nafs (jiwa), al-‘aql (akal), al-nasl (keturunan), dan al-mâl (harta).5 Guna mewujudkan serta memelihara ushûl al-khamsah tersebut, maka maslahat dibagi kepada tiga tingkatan kepentingan, yaitu mashlahah al-dharûriyât, mashlahah al-hâjiyât dan mashlahah al-tahsîniyât. Mashlahah al-Dharûriyât merupakan maslahat yang bersifat esensial atau primer, dimana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik kehidupan di akhirat maupun kehidupan di dunia. Ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia dan merupakan tingkat maslahat yang paling tinggi. Tidak terpenuhinya maslahat tersebut, maka mengakibatkan terancamnya eksistensi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Guna menjaga maslahat ini ada dua solusi yakni, pertama merealisasikan dan mewujudkanya, kedua memelihara kelestarianya. Contoh menjaga agama (hifzh al-dîn) dengan merealisasikan dan melaksanakan kewajiban-kewajiban agama seperti beriman, mengucapkan dua kalimah syahâdah, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, puasa, haji dan lain sebagainya, serta memelihara kelestarian agama dengan berjihad menegakkan al-amru bi al-ma’rûf wa al-nahyi ‘an al-munkar.6 Mashlahah al-Hâjiyât merupakan maslahat yang bersifat menyempurnakan atau sekunder, dimana kemaslahatan tersebut dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terealisasinya maslahat ini akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan yang berimplikasi tidak sampai mengancam eksistensi kehidupan Implementasi Maqâshid Al-Syarî’ah dalam Putusan Bahts Al-Masâ’il _297 manusia. Contoh dalam bidang ibadah, diberikanya rukhshah meringkas (qashr) shalat dan berbuka puasa bagi orang sakit dan musâfir.7 Mashlahah al-Tahsîniyât merupakan maslahat yang bersifat pelengkap atau tersier, dimana kemaslahatan tersebut sebagai penunjang tingkat martabat (muru’ah) guna meraih kabaikan dan akhlak yang mulia. Tidak adanya maslahat ini, tidak sampai merusak, mengancam ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Contoh dalam bidang ibadah, menghilangkan najis, menutupi aurat, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunah.8 Pembagian kemaslahatan ini perlu dilakukan guna menentukan tingkat kebutuhan dan skala prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Dalam hal ini berarti kemaslahatan tingkat al-dharûriyât lebih didahulukan daripada kemaslahatan tingkat al-hâjiyât, dan kemaslahatan tingkat al-hâjiyât lebih didahukan daripada kemaslahatan tingkat al-tahsîniyât. 2. Bahts al-Masâ’il dalam Nahdlatul Ulama Sebagaimana dipaparkan di awal, bahwa bahts al-masâ’il di kalangan Nahdlatul Ulama (NU) diyakini sebagai tradisi intelektual, tumbuh dan berkembang sebelum NU berdiri, kemudian dilestarikan dan dilembagakan pasca NU berdiri. Sebetulnya Bahts al-Masâ’il telah berkembang di tengah masyarakat Muslim tradisional pesantren jauh sebelum tahun 1926 dimana NU didirikan. Saat itu sudah ada tradisi diskusi di kalangan pesantren yang melibatkan kiyai dan santri yang hasilnya diterbitkan dalam buletin LINO (Lailatul Ijtima Nahdlatul Oelama). Dalam buletin LINO, selain memuat hasil Bahts al-Masâ’il juga menjadi ajang diskusi interaktif jarak jauh antar para ulama. Seorang kiyai menulis ditanggapi kiyai lain, begitu seterusnya.9 Menurut Martin van Bruinessen, tradisi Bahts al-Masâ’il yang berkembang di kalangan NU bukanlah murni dari gagasan para kyai dan ulama NU. Melainkan tradisi yang diimpor dari Tanah Suci Makkah. Tradisi tersebut sudah ada di Tanah Suci Makkah yang disebut dengan 298_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 tradisi halaqah.10 Tradisi halaqah inilah yang diadopsi oleh para santri Indonesia yang belajar di Tanah Suci Makkah, ketika mereka pulang ke tanah air Indonesia, sistem halaqah diterapkan di lembaga pendidikan pesantren guna mengkaji persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Adapun sistem pengambilan keputusan dalam Bahts al-Masâ’il Nahdlatul Ulama dirumuskan dalam tiga prosedur. a. Prosedur Pemilihan Qawl/Wajah 1) Ketika dijumpai beberapa qawl/wajah (pendapat) dalam satu masalah yang sama, maka dilakukan usaha memilih salah satu pendapat. 2) Pemilihan salah satu pendapat dilakukan dengan tata urutan sebagai berikut: a) Dengan mengambil pendapat yang lebih mashlahah dan atau yang lebih kuat. b) Sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan Muktamar NU ke-I, bahwa perbedaan pendapat diselesaikan dengan memilih: • Pendapat yang disepakati oleh al-Syaykhân (Nawawi dan Rafi’i) • Pendapat yang dipegangi oleh Nawawi saja • Pendapat yang dipegangi oleh Rafi’i saja • Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama • Pendapat ulama terpandai • Pendapat ulama yang paling warâ‘ b. Prosedur Ilhâq Dalam hal ketika suatu masalah atau kasus belum dipecahkan dalam kitab, maka masalah atau kasus tersebut diselesaikan dengan prosedur ilhâq al-Masâ’il bi Nazhâ’irihâ (mempersamakan hukum suatu kasus yang belum ada ketentuan hukumnya dengan kasus yang mirip yang telah Implementasi Maqâshid Al-Syarî’ah dalam Putusan Bahts Al-Masâ’il _299 ada ketentuan hukumnya dalam kitab fikih) secara jamâ‘i (kolektif). Ilhâq dilakukan dengan memperhatikan mulhaq bih (kasus yang telah ada ketentuan hukumnya dalam kitab-kitab fikih), mulhaq ilayh (kasus yang hendak dicari hukumnya atau dipersamakan hukumnya) dan wajh alilhâq (sifat yang mempertemukan antara mulhaq bih dengan mulhaq ilayh) oleh para mulhiq (ulama penggali hukum) yang ahli. c. Prosedur Istinbâth Dalam hal ketika tak mungkin dilakukan al-ilhâq karena tidak adanya mulhaq bih dan wajh al-ilhâq (sisi persamaannya) sama sekali di dalam kitab, maka dilakukan istinbâth secara jamâ’i yaitu dengan mempraktekkan qawâ’id al-ushûliyyah dan qawâ’id al-fiqhiyyah oleh para ahlinya.11 3. Perkawinan Beda Agama dalam Pandangan Fikih a. Wanita Muslimah dengan lelaki non-Muslim (Musyrik dan Ahl al-Kitâb) Para ulama sepakat bahwa wanita Muslimah tidak boleh (haram) dinikahkan dengan lelaki non-Muslim, baik dari kelompok Musyrik (penyembah berhala) maupun Ahl al-Kitâb.12 Pengharaman ini berdasarkan surat al-Baqarah/2 ayat 221 dan surat al-Mumtahanah/60 ayat 10. Larangan atau pengharaman wanita Muslimah menikah dengan lelaki Musyrik, meskipun pandangan mayoritas ulama tidak memasukan Ahl-al-Kitâb dalam kelompok yang dinamai Musyrik, bukan berarti ada izin untuk pria Ahl al-Kitâb mengawini wanita Muslimah. Menurut surat al-Baqarah/2 ayat 221 larangan tersebut berlanjut hingga mereka beriman, sedangkan Ahl al-Kitâb tidak dinilai beriman dengan iman yang dibenarkan Islam. Bukankah mereka –walau tidak dinamai Musyrik – dimasukan ke dalam kelompok Kafir? Ini dapat dipahami pula dari surat al-Mumtahanah/60 ayat 10 bahwa wanita-wanita Muslimah tidak diperkenankan juga mengawini atau dikawinkan dengan pria 300_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 Ahl al-Kitâb. Dalam ayat tersebut meskipun tidak menyebutkan istilah Ahl al-Kitâb, tetapi menyebutkan istilah al-Kawâfir “orang-orang kafir”, sedangkan Ahl al-Kitâb adalah termasuk salah satu kelompok orangorang Kafir. Dengan demikian, walaupun ayat ini tidak menyebut Ahl al-Kitâb, namun ketidakhalalan tersebut tercakup dalam kata al-Kawâfir “orang-orang kafir.”13 b. Laki-laki Muslim dengan wanita Musyrik Para ulama sepakat bahwa laki-laki Muslim dilarang menikahi wanitawanita Musyrik (penyembah berhala).14 keharaman ini sebagaimana wanita Muslimah haram menikah dengan lelaki Musyrik. Berdasarkan surat al-Baqarah/2 ayat 221. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa bagi seorang Muslim haram melakukan pernikahan dengan orang Musyrik, baik laki-laki maupun Wanita, karena antara orang Muslim dengan orang Musyrik terdapat perbedaan yang sangat mendasar tentang masalah keyakinan (i’tiqâdiyah) yang tidak mungkin dapat dipertemukan, yakni antara ketauhidan dan keberhalaan. Hal ini tentu mengakibatkan keluarga sakînah mawaddah wa rahmah yang merupakan harapan dari sebuah ikatan perkawinan tidak akan pernah terwujud. Menurut Rasyîd Ridhâ, yang dimaksud orang Musyrik sabagaimana dalam ayat tersebut adalah orang Musyrik Arab saja pada masa Nabi.15 Hal ini ditunjukan dengan redaksi dalam surat al-Baqarah/2 ayat 221, disamping melarang pernikahan dengan orang Musyrik juga diikuti anjuran menikah dengan budak. Jelas konteksnya adalah orangorang Musyrik Arab zaman Nabi, dan sekarang sudah tidak ada lagi sebagaimana halnya budak.16 Jika diperhatikan, bentuk ungkapan “almusyrikât dan al-musyrikîn” tersebut menggunakan ungkapan plural dan diimbuhi al-ma‘rifah (the definite article). Dalam ilmu tata bahasa (gramatikal) Arab, bentuk ini menerangkan keseluruhan (li al-istaghrâq). Dari sini dapat dipahami bahwa larangan perkawinan dengan wanita Musyrik tanpa pandang bulu dan batas regional, apakah itu dari Musyrik Arab atau bukan. Implementasi Maqâshid Al-Syarî’ah dalam Putusan Bahts Al-Masâ’il _301 c. Laki-laki Muslim dengan wanita Ahl al-Kitâb Berdasarkan zhâhir nash dalam surat al-Mâ’idah/5 ayat 5, perkawinan antara lelaki Muslim dengan wanita Ahl al-Kitâb hukumnya boleh. Menurut jumhur ulama, kebolehan pria Muslim menikah dengan wanita Ahl al-Kitâb adalah bahwa Ahl al-Kitâb merupakan kelompok tersendiri yang berbeda dari golongan Musyrik meskipun masih dalam kategori golongan Kafir. Kemusyrikan dan kekufuranya berbeda dari kemusyrikan kelompok yang lain. Semua ini dapat dipahami dari penyebutan lafad Ahl al-Kitâb dihubungkan (ma‘thûf) dengan lafad almusyrikîn dalam surat al-Bayyinah/98 ayat 1. Sedangkan penghubungan dengan menggunakan huruf “‘athaf waw” memberikan petunjuk bahwa terdapat perbedaan antar Ahl al-Kitâb dengan Musyrik.17 C.Keputusan Lajnah Bahts al-Masâ’il Nahdlatul Ulama Tentang Perkawinan Beda Agama NU mengeluarkan fatwa tentang perkawinan beda agama, sebanyak tiga kali. Pertama oleh Keputusan Konferensi Besar Pengurus Besar Syuriah Nahdlatul Ulama Ke-1 di Jakarta yang diselenggarakan pada tanggal 21-25 Syawwal 1379 H/18-22 April 1960 M. Dalam Konferensi tersebut diputuskan bahwa perkawinan antara lelaki Muslim dengan perempuan Kafir hukumnya tidak boleh/haram dan tidak sah. Keharaman ini apabila perempuan kafir tersebut bukan Kafir Kitabi yang asli.18 Dasar hukum yang diambil oleh NU adalah Kitab Tuhfah al-Thullâb bi Syarh al-Tahrîr dan Hâsyiyah al-Syarqawi juz II. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa hanya perempuan Ahl al-Kitâb yang asli saja perkawinan beda agama ini boleh dilaksanakan, yang berarti halal. Adapun Ahl al-Kitâb menurut Zakariya al-Anshârî ada dua, yaitu Isrâiliyah dan bukan Isrâiliyah. Wanita-wanita isrâiliyah tersebut boleh dinikahi apabila orang tuanya masuk ke dalam agama tersebut sebelum dinaskh dengan kerasulan Nabi Muhammad. Sebaliknya, apabila orang tuanya masuk ke agama tersebut setelah dinaskh dengan kerasulan Nabi Muhammad maka hukumnya tidak boleh dan haram. Wanita-wanita yang dimaksud adalah anak cucu Yakub 302_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 ibn Ishâq ibn Ibrâhîm. Sedangkan wanita-wanita yang bukan Isrîiliyah, boleh dinikahi apabila agama orang tuanya diketahui bahwa agama yang dianutnya tersebut belum dinaskh dengan kerasulan Nabi Muhammad. Adapun yang dimaksud dengan wanita bukan Isrâiliyah adalah orangorang Arab dan sekitarnya (‘Ajam) seperti Turki yang mengikuti agama Yahudi dan Nasrani.19 Dengan kata lain, bahwa boleh menikahi wanita Ahl al-Kitâb dengan catatan nenek moyangnya sudah menjadi Ahl alKitâb sejak masa Nabi Muhammad. Jadi, bolehnya menikahi mereka karena menghormati asal usul keturunannya saja. Hal ini ditunjukan dengan kata min qablikum (dari sebelum kamu) ayat yang dijadikan dasar kebolehan menikahi wanita-wanita Ahl al-Kitâb (QS. al-Mâ’idah/5 ayat 5. Kedua Keputusan Muktamar Ke-IV Jam’iyah Thariqah Mu’tabarah di Semarang pada tanggal 4-7 Sya’ban 1388 H/28-30 Oktober 1968 M. Dalam Muktamar tersebut juga menyepakati tentang tidak sahnya perkawinan seorang Muslim dengan wanita Kristen, meskipun dilakukan dengan dua kali akad. Begitu juga sebaliknya, seorang wanita Muslimah dengan seorang lelaki non-Muslim tidak sah. Dan walinya haram melakukan perkawinan tersebut, sebab telah melakukan akad yang batal, sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh para ulama.20 Keputusan tersebut berdasarkan kedua kitab Fath al-Mu‘în dan I‘ânah al-Thâlibîn. Dalam kedua kitab tersebut, dijelaskan bahwa termasuk salah satu syarat bagi mempelai wanita adalah harus beragama Islam atau tergolong wanita Kitâbiyah murni, yakni Yahudi dan Nasrani. Kebolehan dengan wanita Kitâbiyah inipun ada indikasi makruh. Hal ini menunjukan bahwa kesamaan agama atau akidah bagi kedua mempelai merupakan salah satu asas perkawinan Islam. Karena tujuan perkawinan adalah untuk mencari ketenangan dan kebahagiaan jiwa berdasarkan syari’at, untuk menggapai keridlaan Tuhan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, wanita Kitâbiyah yang murni diperbolehkan karena ada kesamaan akidah yakni mereka hanya mengakui Tuhan satu; Allah. Bagi Kitâbiyah yang akidahnya sudah terkontaminasi dengan keyakinan trinitas, maka tidak halal. Dengan demikian, pada dasarnya perkawinan dengan Kitâbiyah Implementasi Maqâshid Al-Syarî’ah dalam Putusan Bahts Al-Masâ’il _303 juga dilarang, hal ini ditunjukan dengan adanya indikasi makruh menikahinya. Ketiga, Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-28 di Yogyakarta pada tanggal 26-29 Rabi’ul Awal 1410 H/25-28 Nopember 1989 M. Pada dasarnya keputusan Muktamar ini sebagai pengukuhan atas keputusankeputusan sebelumnya, yakni Keputusan Konbes ke-1 di Jakarta 1960 dan Keputusan Muktamar Ke-IV Jam’iyah Thariqah Mu’tabarah di Semarang 1968. Begitu juga dengan landasan keputusan hukum tersebut, tidak jauh berbeda dengan kedua keputusan sebelumnya. Yakni kitab alSyarqâwî ‘Alâ al-Tahrîr, ditambah kitab al-Muhadzdzab. Keputusan yang sudah disepakati tersebut menyatakan bahwa hukum pernikahan antara dua orang yang berlainan agama di Indonesia hukumnya tidak sah. D.Implementasi Teori Maqâshid al-Syarî’ah dalam Perkawinan Beda Agama 1. Hifzh al-Dîn Menurut KH. Arwani, salah satu hikmah dibolehkannya menikah dengan wanita Ahl al-Kitâb adalah kalau lelakinya itu Muslim maka lelaki itu akan mengatur rumah tangganya. Dan lelaki yang menjadi pemimpin rumah tangga tidak akan mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran Ahl alKitâb. Dengan demikian suami Muslim mampu membina pendidikan anak-anaknya secara Islami.21 Sedangkan KH. Zulfa mengatakan bahwa hikmah dibolehkannya lelaki Muslim menikah dengan wanita Ahl al-Kitâb adalah untuk berdakwah kepada mereka. Dengan harapan mereka bisa mengikuti agama yang dianut suaminya, Islam.22 Jika kondisi justeru sebaliknya, isteri (Ahl al-Kitâb) yang berperan aktif dalam mengatur rumah tangganya, atau justeru suami (Muslim) akan terbawa kepada agama yang dianut isterinya (Ahl al-Kitâb), maka hukum boleh (mubâh) dapat berubah menjadi haram. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Syaltût bahwa ketika Allah melarang wanita Muslimah menikah dengan lelaki Ahl al-Kitâb karena untuk menjaga pengaruh kekuasaan dan dominasi 304_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 suaminya terhadap wanita muslimah, maka Islam juga memandang bahwa sesungguhnya jika pria Muslim telah bergeser dari posisi yang semestinya dalam keluarga, dan menyerahkan urusan keluarga kepada isterinya yang bukan Islam, maka Islam melarangnya untuk mengawini wanita Kitâbiyah tersebut.23 Larangan perkawinan tersebut sudah dimulai pada masa sahabat, ‘Umar ibn Khaththab adalah salah satu sahabat yang melarang perkawinan beda agama24 dengan alasan siyâsah syar‘iyyah. Beliau menghimbau kepada para sahabat untuk tidak megawini wanita Ahl al-Kitâb karena kekhawatiranya terhadap sikap lelaki Muslim yang lebih cenderung memilih wanita Kitâbiyah karena kecantikanya dari pada wanita Muslimah, sehingga akan menimbulkan fitnah dikalangan wanita Muslimah. Larangan ‘Umar ibn Khaththab jika diperhatikan hanyalah untuk menghindari mafsadah atau bahaya. Bahaya yang akan ditimbulkan akibat perkawinan beda agama dipandang lebih besar dari pada manfaat yang akan didapatkanya. Dalam kajian qawâ’id al-ushuliyyah metode ini disebut dengan sadd al-dharî‘ah yakni upaya pencegahan atau tindakan preventif untuk menolak kerusakan atau menyumbat jalan yang menyampaikan seseorang kepada kerusakan. Sedangkan dalam kajian qawâ’id al-fiqhiyyah kaidah tersebut dikenal dengan dar’u al-mafâsid muqaddam ‘alâ jalb al-mashâlih yakni menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kebaikan. Penggunaan metode sadd al-dzarî‘ah dalam penetapan hukum yang perlu diperhatikan oleh para ahli hukum adalah bahwa dzarî‘ah (jalan) yang akan membawa kepada mafsadah harus ditetapkan berdasarkan penelitian yang seksama. Penulis telah mengidentifikasi berbagai hal yang dianggap NU sebagai kemudaratan atau mafsadah yang ditimbulkan akibat perkawinan dengan wanita Ahl al-Kitâb. Mafsadah tersebut adalah perpindahan agama suami (Muslim) kepada agama yang diikuti oleh isterinya (Ahl al-Kitâb) dan agama anak sama dengan agama yang diikuti oleh ibunya.25 Menurut NU, menjaga agama (hifzh al-dîn) baik untuk diri sendiri maupun orang lain bahkan untuk memperkuat komitmen semua Implementasi Maqâshid Al-Syarî’ah dalam Putusan Bahts Al-Masâ’il _305 umat beragama terhadap ajaran agamanya menempati prioritas di atas segala-galanya atau darûriyât.26 Dengan demikian hifzh al-dîn merupakan suatu hal yang sangat esensial karena hifzh al-dîn merupakan salah satu tujuan disyari’atkan hukum Islam. Maslahat sebagai inti tujuan syari’at (maqâshid al-syarî‘ah) atau filosofi ajaran Islam yang hendak dicapai dari larangan perkawinan antar agama adalah untuk merealisasikan hifzh al-dîn. Beragama adalah suatu keharusan bagi semua orang, sebab nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa oleh ajaran agama manusia menjadi lebih tinggi derajatnya dari derajat hewan. Agama adalah salah satu ciri khas manusia. Dalam memeluk suatu agama, manusia harus memperoleh rasa aman dan damai, tanpa adanya intimidasi. Dalam rangka memelihara dan mempertahankan kehidupan dan agama serta membentengi jiwa dengan nilai-nilai keagamaan itulah, maka berbagai macam ibadah disyari’atkan. Ibadah ini dimaksudkan untuk membersihkan jiwa dan menumbuhkan semangat keberagamaan.27 Oleh karena itulah, pada dasarnya manusia membutuhkan agama secara mutlak. Tanpa agama tidak ada gunanya hidup, bahkan agama adalah kebutuhan paling utama dari semua kebutuhan pokok. Untuk melindungi kehormatan agama, syari’at menetapkan hukuman yang berat bagi kejahatan agama. Agama menempati urutan pertama dalam tujuan syari’at, sebab keseluruhan Ajaran syari’at mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak-Nya dan keridlaan Tuhan. Karena itu di dalam Al-Qur’an dan Hadits manusia didorong untuk beriman kepada Allah, dan inilah yang menjadi prinsip perkawinan. Adapun hubungan perkawinan dengan aspek akidah ini memungkinkan perkawinan dalam Islam menjadi sebuah ibadah.28 Dengan memperhatikan mafsadah yang akan ditimbulkan akibat perkawinan beda agama, yakni perpindahan agama suami (Muslim) kepada agama yang diikuti oleh isterinya dan agama anak sama dengan agama yang diikuti oleh ibunya, maka sudah seharusnya perkawinan tersebut dicegah, dengan pertimbangan perkawinan itu menimbulkan 306_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 mafsadah, dan mafsadah-nya sudah pasti terjadi. Pencegahan mafsadah tersebut dengan cara melarang perkawinan itu. Dengan pencegahan itulah, maka maslahat sebagai inti dari Maqâshid al-Syarî’ah akan terwujud. Sebab maslahat bisa diwujudkan dengan dua cara, pertama dengan menghindari mafsadah (kerusakan) dan kedua dengan mewujudkan 29 kemaslahatan itu sendiri درء املفاسد وجلب املنافع. Menjaga al-dîn (agama) dari kerusakan, merupakan suatu hal yang harus dilakukan, karena menjaga al-dîn merupakan dharûriyyat yang paling besar dan terpenting, maka syari’at mengharamkan berbagai macam bentuk riddah (Murtad), serta memberi sanksi kepada orang yang Murtad dan dibunuh. Pada dasarnya beragama merupakan fitrah bagi manusia, beragama merupakan panggilan naluri jiwa. Karena jiwa sebelum masuk ke dalam jasad manusia, ia telah dipersaksikan oleh Tuhannya.30 Dengan persaksian tersebut, maka beragama yang merupakan fitrah manusia harus dijaga, mengabaikannya berarti menelantarkanya, sehingga palakunya harus dikenakan sanksi. Untuk menjaga agama yang merupakan fitrah manusia sejak lahir itulah, maka Allah mensyari’atkan ibadah kepada hambanya. Agar dengan ibadah tersebut manusia akan selalu ingat terhadap Tuhannya. Sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam firmannya surat al-Dzâriyat/51 ayat 56 َوَما َ َ ْق ُت ْقا َّن َو ْقا ْق َ َّن ََي ْق ُت ُت وو Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah-Ku. Demikian tujuan hakiki dari penciptaan makhluk. Oleh karena itu, segala aspek kehidupan manusia (Mu’min) baik yang berhubungan dengan Tuhan langsung (vertikal) maupun dengan sesama (horizontal) akan dinilai sebagai ibadah manakala diniatkan untuk mengabdi kepada Allah. Namun sebaliknya jika perbuatan tersebut tidak didasari Implementasi Maqâshid Al-Syarî’ah dalam Putusan Bahts Al-Masâ’il _307 niat untuk mengabdi kepada Allah, maka perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai ibadah, karena ibadah memerlukan sebuah niat, sedangkan salah satu syarat niat adalah Islam. Dengan demikian, orang melakukan perkawinan beda agama yang disinyalir terjadi pemurtadan maka sudah barang tentu harus dilarang demi untuk menjaga agama pelaku kawin beda agama. Pemurtadan, baik yang dialami oleh suami maupun anak merupakan madarat yang sangat besar, sebab agama merupakan salah satu sendi darûriyyât al-khamsah yang wajib dijaga oleh setiap individu dan juga oleh bersama-sama. Agama dalam darûriyyât alkhamsah merupakan darûriyyât yang paling urgen dibandingkan dengan darûriyyât yang lain. Oleh karena itu, mencegah kemudaratan akibat dari perkawinan beda agama harus didahulukan daripada mengambil manfaat dari perkawinan beda agama. 2. Hifzh al-Nasl a. Keharmonisan Rumah Tangga Kemaslahatan perkawinan yang berupa meneruskan keturunan merupakan termasuk mashlahat dharûriyyât. Penyaluran kebutuhan biologis secara benar (tidak zina) merupakan maslahat hâjjiyyah. Sedangkan kemaslahatan yang berupa kelanggengan ikatan perkawinan, keharmonisan rumah tangga, saling berbagi kasih sayang, ketenangan dan cinta adalah maslahat tahsiniyah.31 Terwujudnya suasana keluarga yang tenang, penuh dengan kasih dan sayang (sakînah mawaddah wa rahmah), merupakan dambaan setiap pasangan suami dan isteri yang telah mengikatkan dirinya dalam ikatan (akad) perkawinan. Sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.32 Kehidupan keluarga yang diliputi dengan suasana tenang, penuh kasih dan sayang, barang kali inilah yang digambarkan oleh Nabi Muhammad bahwa rumah tangga adalah surga 308_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 di dunia baytî jannatî (rumahkau surgaku). Rumah sebagai tempat untuk mendatangkan ketenangan dan ketentraman bagi anggota keluarga. Dalam surat al-Rûm ayat 21 menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakînah mawaddah wa rahmah. Sakînah, dimana angggota keluarga hidup dalam keadaan tenang dan tentram, seia sekata sehingga tercipta rasa kedamaian. Mawaddah, kehidupan anggota keluarga dalam suasana kasih mengasihi, butuh membutuhkan, hormat menghormati satu sama lainnya. Rahmah, pergaulan keluarga dengan sesamanya saling menyayangi, cinta mencintai sehingga kehidupan diliputi rasa kasih sayang. Hal ini menunjukan bahwa, membentuk rumah tangga yang diliputi oleh suasana bahagia, harmoni, tentram, sakînah, cinta mencintai (mawaddah), dan kasih mengasihi (rahmah), merupakan tujuan hal yang mesti dicapai dalam rumah tangga. Dalam istilah disebutkan bahwa dalam perkawinan harus “silih asuh (saling bina membina), silih asah (saling menerima dan memberi), dan silih asih (saling kasih mengasihi)”. Sehingga pada gilirannya, mampu menciptakan satu kesatuan yang terpadu (integrated). Hal ini berdampak bukan saja menciptakan suasana yang mesra dikalangan keluarga, akan tetapi juga memancarkan kemesraan pada orang lain, terutama kapada tetangga dan lingkungannya.33 Akan tetapi, tidak jarang justeru terjadi sebaliknya, rumah tangga yang didambakan sebagai surga di dunia “baytî jannatî” malah menjadi neraka di dunia. Mereka tidak dapat menikmati kebahagiaan yang diperoleh lewat perkawinannya. Ikatan rumah tangga retak (broken home). Pintu perceraian selalu terbuka. Setiap saat ditiup badai pertengkaran dan percekcokan. Anak-anak terlantar, nakal, durhaka, tamak dan serakah. Semua itu merupakan masalah keluarga yang harus diselesaikan. Perkawinan merupakan pembentukan keluarga, dan keluarga merupakan batu bata dalam bangunan bangsa. Oleh karena itu, manakala batu bata itu kokoh dan kuat, maka bangunan itu kokoh dan kuat pula, dan begitu pula sebaliknya, jika batu bata yang menyangga bangunan itu rapuh, maka bangunan itu niscaya akan runtuh pula, dan Implementasi Maqâshid Al-Syarî’ah dalam Putusan Bahts Al-Masâ’il _309 sesungguhnya satu bangsa itu terdiri dari kumpulan beberapa keluarga.34 Dengan demikian, soal perkawinan bukan hanya urusan antara dua orang yang bersangkutan (suami dan isteri), melainkan urusan bersama dan harus mendapatkan perhatian penuh dari masyarakat. Oleh karena itulah, setiap agama mengakui bahwa perkawinan merupakan perbuatan suci (sakral). Agama mengatur dan menjunjung tinggi lembaga perkawinan, sebab lewat perkawinan pergaulan laki-laki dan wanita terjalin secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia dan terhormat. Perkawinan yang akan melahirkan keluarga sakînah mawaddah wa rahmah, adalah perkawinan yang mampu menghadapi berbagai konflik dan juga mampu menyelesaikannya. Konflik selalu ada dalam kehidupan bersama, bahkan dalam hubungan yang sempurna sekalipun. Untuk menciptakan suasana keluarga bahagia, tentram dan harmonis diperlukan masing-masing pasangan suami-isteri memiliki kualitas interaksi perkawinan yang tinggi. Dalam kehidupan suatu perkawinan, terkadang apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Perkawinan menuntut adanya perubahan gaya hidup, menuntut adanya penyesuaian diri terhadap tuntutan peran dan tanggung jawab baru baik dari isteri maupun suami. Ketidakmampuan melakukan tuntutantuntutan tersebut tidak jarang menimbulkan pertentangan, perselisihan dan bahkan berakhir dengan perceraian.35 Konflik yang terjadi dalam kehidupan keluarga, merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari, akan tetapi harus dihadapi. Ini karena dalam suatu perkawinan terdapat penyatuan dua pribadi yang unik dengan membawa sistem keyakinan masing-masing berdasar latar belakang budaya serta pengalaman yang berbeda-beda. Perbedaan yang ada tersebut, perlu disesuaikan satu sama lain untuk membentuk sistem keyakinan baru bagi keluarga mereka. Proses inilah, yang seringkali menimbulkan ketegangan, ditambah lagi dengan sejumlah perubahan yang harus mereka hadapi, seperti perubahan kondisi hidup, perubahan 310_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 kebiasaan dan atau perubahan kegiatan sosial. Menurut Sadarjoen, sumber konflik perkawinan yang saling berpengaruh satu sama lain secara dinamis adalah perbedaan yang tidak terelakkan, perbedaan harapan, kepekaan, keintiman dalam perkawinan, aspek kumulatif dalam perkawinan, persaingan dalam perkawinan, dan perubahan dalam perkawinan. Pasangan suami isteri terdiri atas individu yang secara esensial memiliki berbagai macam perbedaan baik dalam pengalaman maupun dalam kebutuhannya. Perbedaan tersebut terkait erat dengan nilai-nilai yang dianut dan nampak peranannya dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah. Secara logika, perbedaan masing-masing dalam memaknai sesuatu memiliki kecenderungan untuk memicu terjadinya konflik sekiranya kedua pasangan tidak mampu menemukan persetujuan secara total dan tidak mampu menerima perbedaan-perbedaan tersebut.36 Perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang syarat dengan konflik. Karena dalam perkawinan tersebut, masing-masing individu mempunyai perbedaan-perbedaan yang bukan hanya masalah kehidupan sehari-hari melainkan masalah-masalah prinsip dalam kehidupan. Dengan peraturan agama masing-masing, mereka terikat pada ketentuan-ketentuan doktrin yang mereka terima dari agama yang dianutnya. Perkawinan beda agama akan menimbulkan berbagai kesulitan di lingkungan keluarga, misalnya dalam hal pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pengaturan tatakrama makan-minum, pembinaan tradisi keagamaan, dan lain sebagainya. Perkawinan tersebut, tidak akan melahirkan interaksi sosial yang istimewa, bahkan dari hubungan tersebut tidak akan didapatinya rasa mawaddah wa rahmah. Berdasarkan tujuan perkawinan yang hendak dicapai, yaitu sakînah mawaddah wa rahmah, maka perkawinan yang ideal adalah suatu perkawinan yang didasarkan pada satu akidah, di samping cinta dan ketulusan hati dari keduanya. Dengan landasan dan naungan keterpaduan itu, kehidupan suami-istri akan tentram, penuh rasa cinta dan kasih sayang. Kehidupan keluarga akan bahagia dan kelak memperoleh keturunan yang sejahtera lahir batin. Berdasarkan ajaran Implementasi Maqâshid Al-Syarî’ah dalam Putusan Bahts Al-Masâ’il _311 Islam, deskripsi kehidupan suami-istri di atas akan dapat terwujud bila suami-isteri memiliki keyakinan agama yang sama, sebab keduanya berpegang teguh untuk melaksanakan satu ajaran agama, yaitu Islam. b. Menjaga Moral Tujuan perkawinan selain untuk mendapatkan keluarga yang sakînah mawaddah wa rahmah, juga untuk menjaga moral. Oleh karena itu, Islam mengharamkan perbuatan zina, sekaligus melegalkan intitusi perkawinan. Dengan demikian, Al-Qur’an mengilustrasikan perkawinan dengan istilah al-Ihshân. Al-Hushn yang berarti benteng pertahanan, kokoh dan kuat. Maka, al-Ihshân berarti berusaha menjaga diri dengan bersembunyi dalam benteng. Dan orang yang menikah disebut alMuhshan, yang berarti bahwa seola-olah dia telah membangun sebuah benteng pertahanan dan benteng penjagaan. Maksudnya ia telah masuk dalam penjagaan benteng ini yang dibangun untuk menjaga moralnya dan dirinya dengan status perkawinannya.37 Dengan demikian salah satu wujud untuk menjaga moral, Allah telah mengharamkan perbuatan zina. Karena disinyalir perbuatan zina akan merusak moral sekaligus mengacaukan jalur keturunan. Lebih dari itu, Al-Qur’an menjelaskan bahwa perbuatan zina termasuk perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat al-Isrâ/17 ayat 32. Ayat tersebut bukan hanya melarang perbuatan zina, akan tetapi segala bentuk perbuatan yang akan mendekatkan diri kepada perbuatan zina juga terlarang. Sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa للوسائل احكام املقاصد “bagi setiap wasîlah (perantara) hukumnya sama dengan hukum tujuan”. Apabila yang dituju itu wajib, maka media menuju kepada yang wajib juga wajib. Sebaliknya apabila yang dituju itu haram, maka usaha menuju yang haram juga haram. Oleh karena itu, segala sesuatu yang bisa menghantarkan atau membuat terjadinya perbuatan zina maka hukumnya sama dengan zina. 312_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 Di sisi lain, Nabi lewat Haditsnya telah memberikan perintah menikah bagi siapa saja yang telah mampu untuk menikah, bagi yang belum mampu, agar menahan diri dengan melakukan ritual puasa, sebab puasa disinyalir mampu menahan nafsu untuk berbuat yang tidak diinginkan. Demikian ayat dan juga Hadits Nabi, dalam upaya menjaga keturunan atau keluarga (Hifzh al-Nasl) yakni melarang perbuatan zina juga sekaligus melarang perbuatan-perbuatan yang bisa menghantarkan kepada perbuatan zina. Sebagai solusinya syari’at memberikan jalan untuk menikah guna terbebas dari perbuatan zina tersebut. Dengan demikian, larangan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh LBMNU terdapat indikasi perbuatan zina di dalamnya. Karena NU menganggap orang-orang Kristen dan yang lainya bukanlah termasuk golongan Ahl al-Kitâb, dikarenakan kitab-kitab yang dijadikan pedoman sudah mengalami berbagai macam perubahan. Perubahan tersebut baik yang berhubungan dengan subtansi maupun teksnya. Perubahanperubahan itulah yang menjadikan mereka tidak dikategorikan sebagai Ahl al-Kitâb, orang-orang Yahudi dan Nasrani mengalami pergeseran tentang ketauhidan. Hal ini dapat diketahui dari pernyataan mereka bahwa Nabi ‘Isa dan ‘Uzayr dianggap sebagai Tuhan,38 yang dengan jelas dalam Al-Qur’an perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan syirik. Keputusan LBMNU, yang menyatakan tentang tidak sah dan haramnya perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang berlainan agama, baik laki-laki Muslim dengan wanita non-Muslim, dan atau wanita Muslim dengan laki-laki non-Muslim, menunjukan bahwa perkawinan tersebut jika tetap berlangsung masuk kategori perbuatan zina. Hal ini dikarenakan secara syar‘i perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Yang berakibat pada tidak halalnya hubungan antara laki-laki dan wanita tersebut. Jika diperhatikan, kemungkinan banyaknya kasus perkawinan beda agama, dikarenakan faktor keagamaan yang disandang oleh pelaku perkawinan tersebut lemah. Yakni keimanan yang lemah Implementasi Maqâshid Al-Syarî’ah dalam Putusan Bahts Al-Masâ’il _313 mengakibatkan terjerumusnya seseorang untuk melakukan perkawinan beda agama, sebaliknya tingkat keagamaan (iman) yang kuat tidak akan menjerumuskan seseorang pada perkawinan beda agama. John Mulhearn menyatakan bahwa releguitas yang kuat akan mampu mengendalikan praktek perkawinan beda agama.39 Dalam salah satu Haditsnya Nabi sudah memperingatkan bahwa seseorang tidak akan melakukan perbuatan zina, selama di dalam hatinya masih ada iman.40 Menurut Hamka dalam perkawinan lebih memilih pada bentuk perkawinan yang ideal, yakni perintah berhati-hati dalam memilih pasangan hidup, karena isteri adalah teman hidup, membantu, menegakkan rumah tangga yang bahagia penuh cinta dan kasih sayang karena iman, mewariskan generasi yang salih dan salihah. Karenanya, perkawinan harus dibangun atas dasar keyakinan yang sama dan harus ditegakan atas dasar kafa’ah (kesempurnan), yaitu masing-masing suami-isteri memiliki pokok dasar, persamaan tujuan, kepercayaan dan anutan agama. Dengan demikian, Muslim tidak sepadan dengan segala perilaku orang-orang yang mempersekutukan Allah, sehingga tidak boleh dilengahkan, karena rumah tangga yang kokoh dibangun atas dasar iman yang kokoh pula, sehingga perkawinan yang bercitacita bahagia dunia-akhirat, serta menggapai ampunan-Nya menjadikan rumah tangga yang ideal dan bahagia, karena persamaan menuju ridho Allah.41 Dengan demikian, perkawinan yang dilaksanakan membawa kemaslahatan untuk individu dan keluarganya. E. Penutup Perkawinan beda agama, merupakan praktek perkawinan yang menyalahi prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam. Prinsip perkawinan dalam Islam, merupakan prinsip yang berlandaskan teori Maqâshid alSyarî’ah yakni prinsip yang berusaha untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia dan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dengan perkawinan tersebut. Secara umum, kemaslahatan perkawinan merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk meraih Maqâshid 314_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 al-Syarî’ah dari perkawinan, baik yang bersifat dharûriyyah, hâjjiyyah maupun tahsîniyyah. Kemaslahatan perkawinan yang termasuk ke dalam kategori mashlahah dharûriyah adalah meneruskan keturunan yang merupakan penjagaan langsung terhadap salah satu al-ushûl al-khamsah yang berupa hifzh alnasl. Kemaslahatan perkawinan yang masuk peringkat mashlahah hâjiyyah adalah kemaslahatan yang merupakan penjagaan secara tidak langsung terhadap aspek al-nasl, seperti menyalurkan kebutuhan biologis secara benar (tidak berzina). Sedangkan kemaslahatan yang masuk kategori peringkat mashlahah tahsîniyyah merupakan kemaslahatan untuk mencari ketenangan (sakînah), membagi cinta dan kasih sayang (mawaddah wa rahmah). Di samping hifzh al-nasl, perkawinan juga disinyalir untuk menyempurnakan keagamaan seseorang. Dengan demikian, secara tidak langsung perkawinan juga dimaksudkan untuk melindungi agama (hifzh al-dîn) seseorang dari segala sesuatu yang bisa mengancam praktek keagamaan orang tersebut. Oleh karena itu, perkawinan beda agama yang dimungkinkan menimbulkan mafsadah lebih besar dari pada kemaslahatannya, yakni perpindahan agama (murtad) oleh salah satu pasangan, dan agama anak lebih cenderung mengikuti agama ibunya (non-Muslim), sudah selayaknya dilarang. LBMNU melalui metode qawlî yang diambil dari pendapat-pendapat ulama, melarang praktek perkawinan beda agama apapun bentuknya. Hal ini berdasarkan beberapa mafsadah yang timbul akibat dilaksanakan perkawinan beda agama. Mafsadah tersebut, adalah perpindahan agama (murtad) bagi salah satu pasangan serta agama anak cenderung mengikuti agama ibunya (non-Muslim), hal ini berdasarkan bahwa ibu lebih sering berinteraksi dengan anak dibandingkan dengan suami. Implementasi Maqâshid Al-Syarî’ah dalam Putusan Bahts Al-Masâ’il _315 Daftar Pustaka Abd al-Baqî, Ibarahim Mahmud, Daur al-Waqf fi Tanmiyat al-Mujtama’ al-Madany (Namudzatun al-Amanah al-‘Ammah li al-Auqof Bidaulat alKuwait), al-Kuwait: al-Amanah al ‘Ammah li al-Auqof, 2006. Ahnan, Maftuh, Rumahku Surgaku, tk., Galaxy, 2008 Aini, Nuryamin, “Fakta Empiris Nikah Beda Agama” dalam Ijtihad Islam Liberal: Upaya Merumuskan Keberagamaan Yang Dinamis. Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 2005, cet 1. al-Maudûdî, Abu al-A‘lâ, Huqûq al-Zawjayni, terj., Abu ‘Amir ‘Izza Rasyid Ismâ‘il, Yogyakarta: Absolut, tt. al-Syâfi’î, Muhamad ibn Idris, al-Umm, Beirut: Dâr al-Fikr, 1980, Juz V. al-Syâthibî, Abû Ishâq, al-Muwâfaqât fi Ushûli al-Syarî’ah, Beirut: Dâr alKutub al-Ilmiyah, 2003, Juz II. al-Zuhaylî, Wahbah, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu. Beirut: Dâr al-Fikr, Juz 9, 1997. al-Zuhaylî, Wahbah, Ushûl al-Fiqh al-Islâmî, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1986, Jilid II. Aqil Bahsoan, “Maslahah Sebagai Maqashid al-Syari’ah” dalam Jurnal INOVASI, Volume 8, Nomor 1, Maret 2011. Bruinessen, Martin Van, Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia, Bandung: Mizan, 1996. Christensen, Harold T. and Barber, Kenneth E, “Interfaith versus Intrafaith Marriage in Indiana” dalam Journal of Marriage and Family, 1967, Vol. 29, No. 3, Published by: National Council on Family Relations Stable URL:http://www.jstor.org/stable/349583 316_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 Davidson, James D. and Widman, Tracy, “The Effect of Group Size on Interfaith Marriage among Catholics” dalam Journal for the Scientific Study of Religion, Sep., 2002, Vol. 41, No. 3, Published by: Wiley on behalf of Society for the Scientific Study of Religion Stable URL: http://www.jstor.org/stable/1387452 Eva Meizara Puspita Dewi dan Basti, “Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Isteri”, dalam Jurnal Psikologi, Desember 2008, Volume 2, No. 1. Hamka, Tafsîr al-Azhar. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982. John Mulhearn, S. J, “Interfaith Marriage and Adult Religious Practice” dalam Journal Sociological Analysis, Spring, 1969, Vol. 30, No. 1, Published by: Oxford University Press Stable URL: http://www. jstor.org/stable/3709931 Masyhuri, Aziz, al-Fuyûdhât al-Rabbaniyah, Surabaya: Khalista, tt. Mudzhar, M. Atho, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988, Jakarta: INIS, 1993. Mulia, Siti Musdah, Muslimah Reformis; Perempuan Pembaru Keagamaan, Bandung: Mizan Pustaka, 2005. Nahdlatul Ulama, Ahkâm al-Fuqâhâ: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes 1926-2010, Surabaya: Khalista dan Lajnah Ta’lif Wan Nashr (LTN) PBNU, 2011. Rasyd, Tafsîr al-Manâr, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1999, Juz II. Sabiq, Al-Sayyid, Fiqh al-Sunnah, Beirut: Dâr al-Kitâb al-‘Arabi, 1985, Juz 2. Sastra, Abd. Rozak A. dkk, Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara), Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jakarta, 2011. Implementasi Maqâshid Al-Syarî’ah dalam Putusan Bahts Al-Masâ’il _317 Shihab, M. Quraish, Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Ciputat: Lentera Hati, 2006, vol. 1. Shihab, M. Quraish, Wawasan Al-Qur’an, Bandung: al-Mizan, 2007. Wawancara dengan Arwani Faishal (Wakil Ketua LBM NU) di gedung PBNU. Rabu 01 Oktober 2014. Wawancara dengan KH. Zulfa (Ketua Umum LBM NU) di kediaman beliau. Jl. Warakas II Gg. II Rt 007/002 Tanjung Priok, Sabtu 15 Oktober 2014. Zahrah, Muhammad Abu, Ushul Fikih, terj., Saefullah Ma’shum dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003. 318_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 Endnotes 1. Muhamad ibn Idrîs al-Syâfi’i, al-Umm, Beirut: Dâr al-Fikr, 1980, Juz V,6-7 2. Abdurrahman Wahid (mantan Presiden RI ke-4) menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, selain Islam ada Hindu, Budha, Kristen, Katolik, Protestan, dan lain-lain. Bahkan yang Islam ada yang santri dan ada yang kejawen. Lihat Koran Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Sabtu, 27 Maret 2004, 11. 3. M. Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988, Jakarta : INIS, 1993, 11. 4. Abd. Rozak A. Sastra dkk, Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara) (Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jakarta 2011), 4-6. Bandingkan dengan Harold T. Christensen and Kenneth E. Barber, “Interfaith versus Intrafaith Marriage in Indiana” dalam Journal of Marriage and Family, Vol. 29, No. 3 (Aug., 1967). Published by:National Council on Family Relations Stable URL:http://www.jstor.org/stable/349583. James D. Davidson and Tracy Widman, “The Effect of Group Size on Interfaith Marriage among Catholics” dalam Journal for the Scientific Study of Religion, Vol. 41, No. 3 (Sep., 2002). Published by: Wiley on behalf of Society for the Scientific Study of Religion Stable URL: http://www.jstor.org/stable/1387452 5. Abu Ishâq al-Syâthibî, al-Muwâfaqât fi Ushûli al-Syarî’ah, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, Juz II, 2003, 8. 6. Ibid 7. Ibid, h. 9 8. Ibid, h. 9 Implementasi Maqâshid Al-Syarî’ah dalam Putusan Bahts Al-Masâ’il _319 9. Sahal Mahfudh “Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU: Sebuah catatan pendek”, dalam A. Ma’ruf Asrori dan Ahmad Muntaha (eds), Ahkâm al-Fuqâhâ: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes 1926-2010 (Surabaya: Khalista dan Lajnah Ta’lif Wan Nashr (LTN) PBNU, 2011), vii. 10. Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisitradisi Islam di Indonesia, Bandung: Mizan, 1996, 34 11. Nahdlatul Ulama, Ahkâm al-Fuqâhâ: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes 1926-2010, Surabaya: Khalista dan Lajnah Ta’lif Wan Nashr (LTN) PBNU, 2011, 472-473 12. Muhamad ibn Idrîs al-Syâfi’i, al-Umm, Beirut: Dâr al-Fikr, 1980, Juz V,6-7 13. M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian AlQur’an, Ciputat: Lentera Hati, 2006, vol.1, 444 14. Al-Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Beirut: Dâr al-Kitâb al-‘Arabi, 1985, Juz 2, 99 15. Rasyîd Ridhâ, Tafsîr al-Manâr, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1999, Juz II, 141-142. 16. Siti Musdah Mulia, Muslimah Reformis; Perempuan Pembaru Keagamaan, Bandung: Mizan Pustaka, 2005, 62 17. al-Shaykh Hasan Khâlid, al-Zawâj bi Ghayr al-Muslimîn, 112-113. Lihat M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an (Bandung: al-Mizan, 2007, cet. Ke-1487 18. Ibid, Nahdlatul Ulama, 314 19. Abî ‘Abd Allah ibn Idrîs al-Syâfi’i, Kitâb al-Umm tahqîq ‘Alî Muhammad dan ‘Âdil Ahmad, Beirut: Dâr Ihyâ al-Turâts al-‘Arabî, 2001, Juz 6, 30-31 320_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 20. Aziz Masyhuri, al-Fuyûdhât al-Rabbaniyah, Surabaya: Khalista, tt., 9899 21. Wawancara dengan Arwani Faishal (Wakil Ketua LBM NU) di gedung PBNU, Rabu 01 Oktober 2014. 22. Wawancara dengan KH. Zulfa (Ketua Umum LBM NU) di kediaman beliau, Jl. Warakas II Gg. II Rt 007/002 Tanjung Priok, Sabtu 15 Oktober 2014. 23. Ibid, Mahmûd Syaltût, 279-280 24. Wahbah al-Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu, Beirut: Dâr al-Fikr, 1997, Juz 9, 6655 25. Nuryamin Aini (pengajar Fakultas Syari’ah UIN Syarif Hidayatullah dan peneliti Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia) menyatakan bahwa pengaruh seorang ibu untuk mendidik anaknya agar mengikuti agama ibunya jauh lebih berhasil dari pada ajakan ayahnya. Dominasi figur ibu tidak bisa dipisahkan dari peran nurturancie-nya dan intensitas waktu yang lebih banyak untuk berinteraksi dengan anak-anaknya. Lihat Nuryamin Aini, “Fakta Empiris Nikah Beda Agama” dalam Ijtihad Islam Liberal: Upaya Merumuskan Keberagamaan Yang Dinamis, Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 2005, cet. Pertama, 219-220 26. Ibid, Nahdlatul Ulama, Ahkâm al-Fuqâhâ, 947 27. Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fikih, terj., Saefullah Ma’shum dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, 549 28. Aqil Bahsoan, “Maslahah Sebagai Maqashid al-Syari’ah” dalam Jurnal INOVASI, Maret 2011, Volume 8, Nomor 1, 116. Perkawinan merupakan salah satu aspek mu’amalah sebagai wadah untuk interaksi antara manusia satu dengan yang lainya, hal ini disebabkan karena Implementasi Maqâshid Al-Syarî’ah dalam Putusan Bahts Al-Masâ’il _321 manusia adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan interaksi dengan yang lainya. Perkawinan itu sebenarnya hanya hubungan relasi saja, hanya saja, kalau sesuatu itu naturnya baik, kalau diniatkan ibadah, maka menjadi ibadah. 29. Jalâl al-Dîn ‘Abd al-Rahmân al-Suyûthî, al-Asybâh wa al-Nazhâ’ir, Semarang: Thaha Putra, tt., 31 30. QS. al-A‘raf /7 ayat 172 31. Wahbah al-Zuhaylî, Ushûl al-Fiqh al-Islâmi, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1986, cet. I, Jilid II, 772 dan 1025. 32. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Bab I Pasal 1 33. Maftuh Ahnan, Rumahku Surgaku, tk. Galaxy, 2008, 14-15 34. Ibid, Mahmûd Syaltût, 141 35. Eva Meizara Puspita Dewi dan Basti, “Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Isteri”, dalam Jurnal Psikologi Volume 2, No. 1, Desember 2008, 43 36. Eva Meizara Puspita Dewi dan Basti, “Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Isteri”, dalam Jurnal Psikologi Volume 2, No. 1, Desember 2008, 43-48 37. Abu al-A‘lâ al-Maudûdî, Huqûq al-Zawjayni, terj., Abu ‘Amir ‘Izza Rasyid Ismâ‘il, Yogyakarta: Absolut, tt., 2 38. QS. al-Tawbah/9: 30, QS. al-M’idah/5: 72 39. John Mulhearn, S. J, “Interfaith Marriage and Adult Religious Practice” dalam Journal Sociological Analysis, Spring, 1969, Vol. 30, No. 1 Published by: Oxford University Press Stable URL: http://www.jstor. org/stable/3709931. 40. Sunan Abû Dawud No. 4691. Hadits ini termasuk Hadits yang mem- 322_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 punyai banyak redaksi, lihat Sunan Ibn Mâjah No. 3936, Sunan al-Tirmidzî No. 2625, Sunan Ibn Hibbân No. 186, Shahîh Bukhârî No. 2475 41. Hamka, Tafsîr al-Azhar, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982, Juz 1-3, 193195 Konsep ‘darajah’ : Solusi Al-Quran dalam Mengatasi Beban Ganda Wanita Karier _323 The concept of ‘darajah’: Quranic Solution In Overcome Dual Load of Career Women Konsep ‘darajah’ : Solusi Al-Quran dalam Mengatasi Beban Ganda Wanita Karier Muhammad Amin Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang email: [email protected] Abstract : Pursuing career is the nature of every human being, male and female, as examplified by the shahabiyat since the early days of Islam and keep continues until today. Nowadays, the career women faced by the double burden problem, especially the khidmatulbait problem (domestic work space). Using a conceptual thematic interpretation perspective, the writer offers concept ‘Darajah’ as a solution for this problem. Darajah means the humility of a man to ease his wife’s burden. This concept is abstacted from QS. al-Baqarah/2: 228 and based on the interpretation of Ibn Jarîr al-Thabarî againt this verse. The writer also quoted the opinion of other mufassir and fiqh experts as explanation of the concept ‘Darajah’. An Applicative step to implement this concept has formulated by writer in the TM3 Formulation (Tafaqquh fi al-Din, Musyawarah, Mulabasah, and Mulazamah) which accompanied by an “end-to-end” commitment. Abstraksi : Meniti Karier merupakan fitrah setiap manusia, pria dan wanita, sebagaimana dicontohkan oleh para shahabiyat sejak masa permulaan Islam dan tetap berlangsung hingga saat ini. Dewasa ini, problem yang dihadapi oleh wanita karier adalah double burden, khususnya beban khidmatul bait (domestic sphare-ruang kerja domestik). Dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik konseptual, penulis menawarkan solusi konsep ‘Darajah’ berupa kerendahan-hati seorang suami untuk meringankan beban-beban istrinya. Konsep ini disarikan dari surat al-Baqarah/2ayat228 dan berlandaskan pada penafsiran Ibnu Jarîr al-Thabarî terhadap ayat ini. Penulis juga mengutip pendapat mufassir lain dan ahli fiqh sebagai penjelasan dari konsep ‘Darajah’. Langkah aplikatif untuk melaksanakan konsep tersebut 324_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 penulis rumuskan dalam rumusan TM3 yaitu Tafaqquh fi al-Din, Musyawarah, Mulabasah, dan Mulazamah yang diiringi dengan komitmen end-to-end. Keywords : Career Woman, Double Burden, Khidmatul Bait, Darajah. A.Latar Belakang Meniti karier merupakan fitrah bagi setiap manusia, pria dan wanita.1 Hal ini diterapkan oleh para shahabiyat sejak masa awal hadirnya Islam. Dewasa ini, seorang wanita yang berkarier berarti telah memilih peran ganda2 (double role) dan telah memikul beban ganda (double burden)3 pada wilayah publik dan domestik. Sebagai kitab petunjuk, al-Qur’an telah memaparkan konsep ‘Darajah’4 sebagai solusi dari masalah ini.\ Himbauan untuk bekerja dalam al-Qur’an diperuntukkan bagi setiap manusia. Himbauan tersebut telah dilakukan oleh para shahabiyat seperti Hafshah binti Umar dalam bidang pendidikan, al-Syifa’ binti Abdullah dalam bidang ekonomi, Nashibah dan Rufaidah binti Sa’ad dalam bidang militer.5 Keikutsertaan wanita dalam wilayah publik terus berlangsung hingga saat ini. Akan tetapi, seorang wanita kerier dituntut untuk menjalankan segala urusan rumah tangga (khidmatul bait) dan juga menyelesaikan segala tanggung jawabnya di ruang publik.6 Dalam konteks keluarga, pembagian beban kerja antara pria dan wanita terkadang tidak merata, bahkan pada beberapa keluarga, beban kerja seorang istri jauh lebih berat dan lebih lama daripada beban kerja suami. Sebagai usaha untuk menjawab problem di atas, maka penulis menawarkan konsep ‘Darajah’ sebagai solusi. Darajah adalah kerendahan hati seorang suami untuk meringankan beban kerja istrinya. Konsep ini terinspirasi dari al-Qur’an. Firman Allah: … Konsep ‘darajah’ : Solusi Al-Quran dalam Mengatasi Beban Ganda Wanita Karier _325 Artinya: ”....Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma´ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. al-Baqarah/2: 228.) Penjelasan mengenai hal ini akan penulis paparkan pada bagian berikutnya disertai dengan pandangan para ulama fiqh tentang wanita karier, masalah khidmatul bait, dan konsep Darajah. Penulis juga mengutip pendapat ulama tafsir dan fiqh tentang status wanita karier dalam perspektif islam. Kajian pada tulisan ini dibagi menjadi menjadi tiga bagian: pertama, Pendahuluan yang berisi latar belakang dan rumusan masalah. Kedua, Pembahasan tentang wanita wanita karier, double burden, dan konsep Darajah. Ketiga, Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. B.Islam dan Beban Ganda Wanita Karier 1. Wanita Karier dalam perspektif Islam Wanita berarti perempuan yang telah dewasa, sementara karier berarti perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, dan sebagainya atau pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju.7 Dengan demikian, wanita karier diartikan sebagai wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi seperti usaha, perkantoran, dan lain sebagainya.8 Hasil penelitian kelompok studi wanita FISIP – UI tahun 1987 menunjukkan beberapa alasan seorang wanita berkeluarga memilih untuk bekerja. Faktor tersebut adalah: Faktor ekonomi seperti menambah penghasilan atau punya penghasilan sendiri, Faktor kepuasan jiwa seperti mengisi waktu luang, ingin lebih berkembang, dan mempraktekkan ilmu.9 Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa wanita turut andil dalam berbagai bidang pekerjaan, seperti buruh kasar, karyawan, atau kepemimpinan.10 326_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 Di dalam al-Qur’an, Allah SWT. secara eksplisit menjelaskan hak dan potensi wanita untuk bekerja pada tiga ayat: QS. al-Nisâ’/4: 32 dan 124, serta QS. al-Nahl/16: 97. Adapun kata ‘bekerja’ secara umum terulang sebanyak 359 kali11 dalam berbagai termnya, yaitu ‘amila, kasaba, fa’ala dan sa’a.12 Term yang digunakan dalam surat al-Nisâ’/4 ayat 32 adalah iktasaba sementara pada dua ayat lainnya Allah SWT. menggunakan term ‘amila. Firman Allah: Artinya:” bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.” (QS. al-Nisâ’/4: 32) Kata iktasaba dalam ayat di atas terbentuk dari kata asal kasaba. Penambahan huruf ta pada kata tersebut menunjukkan arti kesungguhan atau usaha ekstra. Berbeda dengan kasaba yang berarti melakukan sesuatu dengan mudah dan tidak disertai upaya yang sungguh-sungguh.13 Ayat di atas memberikan neraca keadilan bagi pria dan wanita, keduanya memiliki keistimewaan masing-masing dan memiliki potensi untuk melakukan sebuah usaha, pekerjaan, atau meniti karier dengan sungguhsungguh serta profesional. Selain pada ayat di atas, anjuran untuk bekerja juga terdapat dalam ayat 97 surat al-Nahl/16 Allah berfirman:14 Artinya:” Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan Konsep ‘darajah’ : Solusi Al-Quran dalam Mengatasi Beban Ganda Wanita Karier _327 kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. al-Nahl/16: 97) Kata amal shalih berarti segala perbuatan baik yang berguna bagi pribadi, keluarga, kelompok, dan manusia secara keseluruhan. Penggunaan kata man pada ayat ini telah menunjukkan keumuman dan hal itu lebih ditekankan lagi dengan penyebutan pria dan wanita. Dengan begitu ayat ini menghimbau pria dan wanita untuk aktif dalam tindakan baik yang berguna bagi masyarakat secara umum.15 Sebagian ulama memberikan kebolehan kepada seorang wanita untuk bekerja atau berkarier. Quraish Shihab berpendapat bahwa seorang wanita memiliki hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut.16 Cendekiawan lain memberikan syarat bagi wanita yang bekerja untuk tidak bercampur baur dengan pria di luar rumah17 dan berpakaian islami.18 Sementara pada bidang politik, masih terjadi perbedaan pendapat ulama tentang kebolehannya atau ketidakbolehannya wanita memimpin suatu negara.19 Ragam pekerjaan yang dapat dilakukan oleh wanita di luar rumah antara lain: tenaga pengajar seperti guru dan dosen, tenaga kesehatan seperti dokter gigi atau dokter kandungan, kerajinan tangan seperti menyulam dan profesi-profesi lainnya. Pada ranah sosial, beredar anggapan di masyarakat bahwa ruang kerja domestik atau khidmatul bait adalah pekerjaan wanita. Dimulai dari memasak, mencuci, menyapu, mengepel, dan segala urusan rumah tangga lainnya.20 Setiap pekerjaan tersebut harus dilakukan oleh wanita sejak subuh hingga malam hari, khususnya bagi wanita yang tidak berkarier. Anggapan tersebut juga tetap berkembang di kalangan wanita karier sehingga terjadi peran ganda (double role) yang dimainkan oleh mereka. Pada saat yang bersamaan, wanita juga memilkul beban ganda. Seorang wanita dituntut untuk selalu mengurusi kebersihan dan kerapihan 328_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 rumah tangga dan ia juga memiliki beban pekerjaan di luar rumahnya. Hal ini dikenal dengan istilah beban ganda atau double burden. 2. Double Burden dan Problematika Khidmatul Bait. Kata double memiliki arti rangkap atau dua kali (lipat), sementara kata burden berarti beban dan tanggung jawab.21 Kedua kata ini memiliki padanan kata Bahasa Indonesia yaitu “Beban Ganda”. Kata beban berarti tanggungan atau kewajiban yang harus dilakukan, sementara kata ganda berarti lipat atau kali.22 Secara umum, dapat difahami bahwa double burden adalah dua atau lebih beban yang dipikul wanita dalam waktu yang bersamaan. Artinya wanita, khususnya wanita karier, memiliki dua peran yang harus dimainkannya. Peran pertama adalah peran domestik sebagai ibu rumah tangga dan peran kedua adalah peran publik sebagai pekerjaannya di luar rumah.23 Para tokoh feminisme menyatakan bahwa double burden adalah salah satu bentuk manifestasi ketidak-adilan gender. Setidaknya ada lima bentuk manifestasi ketidakadilan gender ini yaitu: marjinalisasi (pemiskinan ekonomi), subordinasi (dianggap tidak penting), stereotipe (pelabelan negatif), violence (kekerasan), dan double burden (beban ganda).24 Teori Mansour Fakih menyatakan bahwa ketidakadilan gender dapat terjadi karena beberapa faktor yaitu: (1) Materi hukum (substanse of the law) berupa tafsiran atau pemahaman agama dalam bentuk fiqh, syarah, dan lainya. (2) Kultur hukum (culture of the law). (3) Sturktur hukum (Structure of law).25 Pada makalah ini Penulis akan mengulas faktor pertama yakni materi hukum (substance of the law) dengan memaparkan hak-hak dan kewajiban seorang wanita, khususnya dalam masalah pembagian kerja, dengan melihat sumber-sumber kitab fiqh dan tafsir terhadap al-Qur’an surat al-Baqarah/2 ayat 228. Allah SWT. telah mengatur berbagai urusan manusia, salah satunya Konsep ‘darajah’ : Solusi Al-Quran dalam Mengatasi Beban Ganda Wanita Karier _329 adalah hubungan antara suami dan istri. Pada surat al-Baqarah ayat 228 Allah SWT. berfirman: Artinya:”Dan mereka (para wanita) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut” (QS. al-Baqarah/2: 228) Ayat tersebut menjelaskan bahwa wanita memiliki hak dan kewajiban yang kadarnya seimbang.26 Di antara berbagai hak dan kewajiban suami istri yang dibahas oleh ulama adalah masalah pengurusan keperluan rumah tangga. Para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban seorang istri mengurusi urusan rumah tangga ini: Pendapat Pertama menyatakan bahwa khdimatul bait adalah kewajiban seorang wanita karena telah menjadi ‘urf sejak zaman Nabi. Pendapat ini dikemukakan oleh Sayyid Sabiq.27 Pendapat Kedua menyatakan bahwa khidmatul bait bukanlah kewajiban seorang wanita namun merupakan kesukarelaan dan salah satu dari akhlak yang terpuji. Pendapat ini disampaikan oleh para ulama fiqh sepeti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i, dan Ibnu Hajar al-Asqalani.28 Pendapat para ‘ulama fiqh ini didukung oleh fakta sejarah yang menunjukkan bahwa sejak masa Nabi Muhammad saw. telah ada adat yang mengatur wanita untuk bekerja pada ruang domestik. Diantara riwayat-riwayat mengenai hal itu adalah: Sayyidah Fatimah ra. selama menikah dengan sayyidah Ali ra. selalu melaksanakan pekerjaan rumah, termasuk memasak dan menggiling gandum. Karena beratnya pekerjaan tersebut maka beliau mengadu kepada sayyidah Aisyah lalu rasul tidak memberikan Fatimah seorang budak tetapi mengajarkannya tasbih. Menurut ulama, ini adalah dalil yang menjelaskan bahwa mengurusi urusan domestik merupakan urusan istri.29 330_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 Riwayat lain menceritakan bahwa Asma binti Abu Bakr melayani suaminya dan membantunya dalam mengerjakan beberapa pekerjaan seperti mengurusi kuda dan lain-lain. Asma’ merasa berat jika harus mengurusi kuda seorang diri maka ayahnya memberikan seorang budak untuk membantu mengerjakan pekerjaan rumahnya.30 Ketika menjadi khalifah, sayyidina Umar ra. pernah menceritakan bahwa istrinya memasak untuk beliau, membuatkan roti, mencuci baju, dan menyusui anak, padahal itu bukanlah kewajiban istrinya. Dan karena itu pula, sayyidina Umar menerima ketika diomeli oleh istrinya dan menasehati pria yang datang kepada beliau untuk melakukan hal yang sama.31 Riwayat-riwayat dan pendapat-pendapat di atas menunjukkan bahwa mengerjakan segala urusan domestik pada dasarnya bukanlah kewajiban seorang istri. Namun melakukan hal tersebut adalah bagian dari akhlak terpuji dan telah dicontohkan oleh para sahabat, istri Nabi, dann juga putrinya sendiri. 3. Konsep ‘Darajah’ sebagai solusi. Pembagian beban kerja yang dikenal di masyarakat Indonesia dewasa ini lebih banyak berpola domestik-publik atau produktif-non produktif. Biasanya, suami akan bekerja sejak pagi hingga sore hari sementara istri akan mengerjakan pekerjaan rumah sejak bangun tidur hingga sesaat sebelum tidur kembali. Persepsi tanggung jawab tugas domestik ini juga terjadi pada wanita karier. Pada bagian sebelumnya Penulis telah memaparkan pendapatpendapat ulama mengenai kewajiban istri dalam mengurus urusan rumah tangga (khidmatul bait). Jika diperhatikan mayoritas ulama atau pendapat Jumhur, maka hal itu bukanlah kewajiban namun merupakan hal yang baik, patut, pantas, dan juga merupakan akhlak yang baik. Akan tetapi, hal ini banyak disalahfahami oleh masyarakat Indoensia sehingga terkadang beban kerja istri jauh lebih berat daripada beban kerja Konsep ‘darajah’ : Solusi Al-Quran dalam Mengatasi Beban Ganda Wanita Karier _331 suami. Misalnya istri yang tidak bekerja di luar rumah akan mengurusi kebutuhan rumah tangga sejak subuh hingga malam, begitu pula wanita karier. Untuk mengatasi hal ini, Allah SWT. telah menjelaskan di dalam alQur’an … Artinya:“....Dan para suami memiliki kelebihan (derajat) di atas mereka.”( Q.S. Al-Baqarah/2 : 228) Ibnu Jarîr al-Thabarî menjelaskan bahwa para ulama tafsir berbeda pendapat mengenai maksud ayat ini. Adapun pendapat-pentapat tersebut adalah: a. Al-fadl atau keutamaan dan kelebihan dalam masalah warisan, jihad dan lainnya b. Kepemimpinan dan ketaatan32 c. Karena mahar yang dibayarkan dan jika seorang suami mencelanya maka ia telah melaknatnya dan jika wanita itu mencela suaminya maka ia dikenai pidana d. Kebaikan kepadanya, memberikan hak wanita, dan kebaikan suami untuk mengurangi beban kewajiban istrinya. Pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Abbas, dan dianggap takwil yang paling tepat oleh al-Thabari dan juga Quraish Shihab.33 Menurutnya al-Thabari, ayat ini bermakna derajat laki-laki itu adalah kerendah-hatiannya untuk membantu istri, meringatkan beban-beban dan kewajiban istri. Sehingga walaupun redaksi ayat ini bentuknya khabar sesungguhnya ayat ini mengandung makna sunnah bagi suami untuk berlaku baik dan membantu istrinya, sehingga mereka akan mendapatkan derajat tersebut.34 Sunnahnya berbuat baik atau membantu istri dalam mengerjakan urusan dan meringankan beban istri ini juga dapat ditemukan dalam beberapa riwayat. Rasulullah saw. jika berada di rumah selalu membantu 332_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 urusan keluarganya hingga tiba waktu adzan. ِ ِ َِّب َ َس َوِد بْ ِن يَِز ُّ ِ َما َكا َن الن،ت َعائ َشةَ َرض َي اللَّهُ َعنْ َها ُ ْ َسأَل،يد ْ َع ِن األ ِ ِ « َكا َن يَ ُكو ُن ِ ِم ْهنَ ِة:ت ْ َ يَ ْ نَ ُ ِ اللَ ْت َال، َ ََّلَّ ااُ َعلَْه َ َسل » َ َ َ َِ َا َِ َ األَ َا َن،َ ْ لِ ِه Artinya:” Dari Aswad ibn Yazid, aku bertanya kepada Aisyah ra. Apa yang dilakukan Nabi saw. di rumah? Aisyah menjawab: Beliau selalu membantu keluarganya, dan jika beliau mendengar adzan beliau keluar (untuk shalat jama’ah).35 Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi saw. pernah bersabda: sebaik-baik kalian adalah orang yang baik kepada kelurganya. Dan aku adalah orang yang paling berlaku baik kepada kelurga di antara kalian.36 Riwayat-riwayat di atas menunjukkan bahwa dalam faham agama Islam secara historis-sosiologis terdapat adat kebiasaan (‘urf) bagi wanita untuk mengerjakan perkara-perkara domestik (khidmatul bait). Namun hal tersebut tidak menghalangi suami untuk berlaku baik, meringankan beban, dan membantu pekerjaan istrinya. Hal ini sesuai dengan ajaran al-Qur’an bahwa kaum mukmin, laki-laki dan perempuan, adalah auliya’ (penolong)37 satu sama lain. 4. Tantangan dan Hambatan: Aplikasi Konsep “Darajah” dalam Konteks Masa Kini Pada bagian sebelumnya Penulis telah memaparkan ragam pandangan ulama fiqh dan mufassir tentang ruang kerja wanita di rumah dan juga solusi yang dapat ditawarkan berupa konsep “darajah” yang bisa dicapai dengan melakukan kebaikan dan meringankan beban kewajiban istri. Tujuannya adalah terciptanya keadilan, kesetaraan dalam kedudukan suami-istri sebagai mitra atau musyarakatul hayat. Konsep ‘darajah’ : Solusi Al-Quran dalam Mengatasi Beban Ganda Wanita Karier _333 Untuk mengaplikasikan solusi tersebut, maka Penulis menawarkan konsep TM3, yaitu: a) Tafaqquh fi al-Din (pendidikan dan pemahaman menyeluruh terhadap sumber-sumber agama, meliputi al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan Qiyas).38 b) Musyawarah (membangun komunikasi yang efektif dalam keluarga, termasuk masalah pembagian beban kerja).39 c) Mulabasah (saling menutupi dan melengkapi dalam membangun relasi suami istri sebagai syarikatul hayat/mitra dalam hidup, bukan relasi majikan-buruh atau patron-klien).40 d) Mulazamah (membangun kebersamaan dalam menghadapi setiap pemasalahan dan saling membantu meringankan beban setiap anggota keluarga).41 Konsep TM3 tersebut dapat diwujudkan dengan adanya sebuah komitmen. Untuk itu, Penulis menawarkan komitmen end to end,42 yaitu totalitas dan ketuntasan dalam bekerja. Dalam konteks perwujudan konsep di atas maka diperlukan tuntas tafaqquh di al-din, tuntas musyawarah, tuntas mulabasah, dan juga tuntas mulazamah. C.Penutup Islam memberikan kesempatan yang setara bagi pria dan wanita untuk meniti karier, hal ini telah dilakukan oleh para shahabiyat hingga para wanita saat ini. Misalnya profesi bidan atau dokter kandungan. Keikut-sertaan wanita dalam tanggung jawab publik tidak disertai dengan kesadaran pembagian beban kerja yang adil di wilayah domestik, sehingga terjadi beban ganda (double burden). Faktor penyebabnya adalah substance of the law, structure of the law, dan culture of the law. Solusi Qurani untuk masalah beban ganda wanita karier adalah konsep Darajah. Konsep ini dapat diterapkan dengan langkah-langkah 334_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 strategis TM3 yaitu, Tafaqquh fi al-Din, Musyawarah, Mulabasah, dan Mulazamah yang diiringi dengan komitmen end-to-end. Penulis menyarankan kepada setiap keluarga muslim untuk menciptakan pola pembagian beban kerja yang baik di lingkungan domestik. Juga mengamalkan kosep Darajah dengan langkah TM3, sehingga akan tercipta keluarga yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebersamaan. Konsep ‘darajah’ : Solusi Al-Quran dalam Mengatasi Beban Ganda Wanita Karier _335 Daftar Pustaka Abdul Baqi, Muhammad Fu’ad, Mu’jam Mufahras li Alfadzi Al-Qur’an, Beirut: Dar al-Fikr, 1994. Al-‘Aini, Badruddin, T.t., Umdatul Qari. Beirut: Dar Ihya al-Turast al‘Araby. Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, T.t., Kamus Kontemporer ArabIndonesia Yogyakarta: Multi Karya Grafika. Al-Asqalani, Ibnu Hajar, Fathul Bari, Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1379 H. Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma’il, Shahih al-Bukhari, Dar Thauq alNajah, 1422 H. Al-Fauzan, Abdul Aziz, Fikih Sosial, Terjemah Iman Firdaus dan Ahmad Solahudin, Jakarta: Qisthi Press. 2007. Al-Haitami, Hafidz, Majma’ Zawaid wa Manba’ al-Fawa’id, Beirut: Dar alFikr, 1992. Al-Jaziri, Abdul Rahman, Al-Fiqhu ‘ala Madzahib al-Arba’ati, Kairo: Dar al-Hadits, 1994. Al-Naisaburi, Abu al-Hasan Muslim, T.t., Shahih Muslim, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-‘Arabi. Al-Qahtany, Muhammad Ahmad Muabbir, Dkk, Pesan Untuk Muslimah. Terjemah Muhammad Sofwan Jauhari, Jakarta: Gema Insani Press, 2002. Al-Thabari, Ibnu Jarir, Jami’ al-Bayan fi Takwil Al-Qur’an, Muassasah alRisalah, 2000. Al-Tirmidzi, Abu ‘Isa, Sunan al-Tirmidzi, Mesir: Musthafa al-Bani, 1975. Al-Utsaimin, Muhammad Shalih, Hak-hak dalam Islam, Terjemah Tarmana 336_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 Ahmad Qasim. Bandung: Trigenda Karya, 1995. Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab, Fiqh Munakahat. Terjemah Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2014. Ba’albaky, Munir, Al-Mawrid: an English-Arabic Dictionary, Beirut: Dar al‘Ilmi, 2001. Chira, Susan, Ketika Ibu Harus Memilih: Pandangan Baru tentang Peran Ganda Wanita Bekerjta, Terjemah Sofia Mansoor, Bandung: Qanita. 1998. Echols, John M. dan Hasan Dhadily, An English-Indonesian Dictionary, Jakarta: Gramedia, 1977. Fakih, Mansour, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001. Ja’far, Muhammad Anis Qasim, Perempuan dan Kekuasaan: menelususri Hak politik dan Persoalan Gender dalam Islam, Terj, Ikhwan Fauzi, Indonesia: Amzah, 2002. Jurnal Analisis Sosial: Analisis Gender dalam Memahami Persoalan Perempuan. Edisi 4 / November 1996. Nawawi, Muhammad ibn Umar, T.t., Syarah uqud al-Lujain, Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah. Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1976. Riyadi, Dodi, ‘Argumen Pemberdayaan Perempuan dalam Islam’ dalam Bimas Islam, 2015, vol. 8 no. 2. Sabiq, Sayyid. T.t. Fiqhu al-Sunnah. Kairo: al-Fath lil I’lam al-‘Arabi. Sajogya, Pudjiwati, Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa, Jakarta: Rajawali, 1985. Konsep ‘darajah’ : Solusi Al-Quran dalam Mengatasi Beban Ganda Wanita Karier _337 Shihab, Muhammad Quraish, Membumikan Al-Qur’an, Bandung: Mizan, 2009. ------------, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, Jakarta: Lentera Hati, 2012. Tapi Omas Ihromi (ed.), Para Ibu yang Berperan Tunggal dan yang Berperan Ganda, Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 1987. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2007. Yasin, Maisar, Wanita Karir dalam Perbincangan, Terjemah Ahmad Thabroni Masudi. Jakarta: Gema Insani Press, 1997. 338_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 Endnotes 1. Himbauan al-Qur’an kepada manusia, pria dan wanita, untuk bekerja dalam al-Qur’an diantaranya terdapat dalam Q.S. al-Nisa’/4: 32 dengan menggunakan kata iktasaba. Lihat juga Q.S. al-Nisa’/4: 124 dan Q.S. alNahl/16: 97. Al-Qur’an juga menjelaskan bahwa fungsi kaum mukmin pria dan wanita adalah auliya’ atau saling tolong. Lihat Q.S. al-Taubah/9: 71 dan Muhammad Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an, Bandung: Mizan, 2009, h. 426. 2. Pembahasan mengenai dua buah peran dan dilema seorang wanita, khususnya ibu atau istri, dalam meilih kedua peran tersebut dapat dilihat dalam Susan Chira, Ketika Ibu Harus Memilih: Pandangan Baru tentang Peran Ganda Wanita Bekerja, terj., Sofia Mansoor, Bandung: Qanita, 1998, h. 303 – 309. Lihat juga Pudjiwati Sajogya, Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa Jakarta: Rajawali, 1985, h. 38. 3. Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, h. 150. 4. Disarikan dari Q.S. al-Baqarah/2: 228. Menurut Quraish Shihab konsep darajah ini berarti kesudian seorang suami untuk meringankan beban-beban istrinya. Lihat Muhammad Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, Jakarta: Lentera Hati, 2012, vol. I., h. 596 – 597. 5. Lihat Muhammad Anis Qasim Ja’far, Perempuan dan Kekuasaan: Menelusuri hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam, terj., Ikhwan Fauzi, Indonesia: Amzah, 2002, h. 65. Lihat Juga Dodi Riyadi, ‘Argumen Pemberdayaan Perempuan dalam Islam’ dalam Bimas Islam, , tahun 2015, vol 8 no. 2, h. 250 -251. 6. Mansour Fakih, Membincang Feminisme, Surabaya: Risalah Gusti, 1996, h. 4849. 7. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, ed. 3 –cet. 4, h. 508 dan 1268. 8. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar ... h. 1268. 9. Tapi Omas Ihromi, ed., Para Ibu yang Berperan Tunggal dan Yang Berperan Ganda, Jakarta: Fakulta Ekonomi UI, 1987, h. 161. 10. Tapi Omas Ihromi, ed., Para Ibu... h. 155. 11. Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Mu’jam Mufahras li Alfadzi al-Qur’an, Beirut: Konsep ‘darajah’ : Solusi Al-Quran dalam Mengatasi Beban Ganda Wanita Karier _339 Dâr al-Fikr, 1994, h. 445 – 446, 613 – 620, 664 – 666, dan 767 – 768. 12. Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, Yogyakarrta: Multi Karya Grafika, t.t., h. 1063, 1322, 1399, dan 1505 13. Muhammad Qurasih Shihab, Tafsir al-Mishbah... vol. II, h. 504. 14. Dalam Q.S. al-Nisa’/4: 124 Allah SWT. menggunakan term ‘amila dalam bentuk mudhari’. 15. Muhammad Qurasih Shihab, Tafsir al-Mishbah... vol. VI, h. 718 – 720. 16. Muhammad Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an... h. 429. 17. Lihat Maisar Yasin, Wanita Karir dalam Perbincangan, terj., Ahmad Thabroni Masudi, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, h. 30. 18. Muhammad Ahmad Muabbir al-Qahtany dkk., Pesan Untuk Muslimah terj. Muhammad Sofwan Jauhari, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h. 52. 19. Lihat Muhammad Anis Qasim Ja’far, Perempuan dan Kekuasaan... h. 40 – 70. 20. Mansour Fakih, Analisis Gender... h. 21 21. John. M. Echols dan Hasan Dhadily, an English-Indonesian Dictionary, Jakarta: Gramedia, 1977, h. 55 dan 88. 22. W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, h. 114 dan 344. 23. Jurnal Analisis Sosial: Analisis Gender dalam Memahami Persoalan Perempuan 1996, Bandung: Akatiga 1996, edisi 4/ novermber, h. 60. 24. Mansour Fakih, Analisis Gender... hlm 12 – 13. 25. Mansour Fakih, Analisis Gender... h. 164. 26. Muhammad Shalih al-Utsaimin. Hak-hak Dalam Islam terj. Tarmana Ahmad Qasim (Bandung: Trigenda Karya, 1995, h. 42 – 51. Mengenai hak-hak dan kewajiban wanita secara umum dapat dilihat dalam Abdul Aziz Dahlan (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996, vol. VI, h. 1920 – 1925. 27. Bandingkan dengan Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi... vol. VI, h. 1921. 28. Sayyid Sabiq, Fiqhu al-Sunnah, Kairo: al-Fath lil I’lam al-‘Arabi, t.t., vol. 2, h. 131. Dan Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Bari, Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1379 H, vol. 9, h. 507. 29. Badruddin al-‘Aini, Umdatul Qari (Beirut: Dar Ihya al-Turast al-‘Araby, t.t.), 340_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 vol XXI h. 20. Bandingkan dengan Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqhu ‘ala Madzahib al-‘Arba’ati (Kairo: Dar al-Hadits, 1994), vol IV h.425. 30. Abu al-Hasan Muslim al-Naisaburi, Shahih Muslim (Beirut: Dar Ihya alTurats al-‘Arabi), vol IV h. 1717 nomor hadis 2182. 31. Muhammad bin Umar Nawawi, Syarah Uqud al-Lujain (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyyah, h. 5. 32. Bandingkan dengan Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab, Fiqh Munakahat, terj. Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2014, h. 222 – 223. 33. Muhammad Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, Jakarta: Lentera Hati, 2012, h. 596 – 597. 34. Ibn Jarir al-Thabari, Jami al-Bayan fi Ta’wil al-Qur’an (T.T.P: Muassasah alRiasalah, 2000, vol IV h. 531 – 537. 35. Muhammad ibn Isma’il al-Bukhari, Shahih Bukhari (T.T.P : Dar Thauq al- Najah, 1422 H.) vol. VII, h. 65. Nomor 5363. Lihat juga Abdul Aziz al-Fauzan, Fikih Sosial, terj. Iman Firdaus dan Ahmad Solahudin Jakarta: Qisthi Press, 2007, h. 151. 36. Abu ‘Isa al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi (Mesir: Musthafa al-Bani, 1975), vol V h. 709 nomor 3895. 37. Q.S. al-Taubah (9) : 71. 38. Q.S. al-Taubah (9) : 122. 39. Q.S. Ali Imran (3) : 159 dan Q.S. al-Syura (42) : 38. 40. Q.S. al-Baqarah (2) : 187. 41. Q.S. al-Taubah (9) : 71. 42. Disarikan dari hadis Nabi Muhammad saw. dari Aisyah ra. Beliau bersabda; “sesungguhnya Allah SWT. menyukai seseorang di antara kalian yang melakukan sebuah perbuatan dengan tuntas (an yutqinahu : teliti dan sempurna).” Lihat Nuruddin ‘Ali ibn Abi Bakar Hafidz al-Haitsami, Majma’ Zawaid wa Manba’ al-Fawa’id (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), vol. IV h. 122. Bandingkan dengan Agus Jaya, ‘The Rola of Religious Affairs Office (KUA)’ in Handling Sempalan Sect: Study Case of Religious Affairs Office (KUA) Tanjung Batu District’ dalam Jurnal Bimas Islam vol. 8, no. 2. Tahun 2015, h. 221. Pengaruh Agama Islam Terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia _341 The influence of Islamic Religion againstthe Legal Developments in Indonesia Pengaruh Agama Islam Terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia Fabian Fadhly Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung email: [email protected] Abstract : The entry of Islam to Indonesia in the first century of Hijri or seventh century of A.D which given influences to many aspect in Indonesian life, one of them is in the field of law. The influence of Islam against the law in Indonesia began to be felt with the rise of Islamic law being introduced and applied in public life of Indonesia together with customary law at the time. Setbacks Islamic law in Indonesia began when the Dutch applied receptie theory, this theory pressing enforceability and implementation of Islamic law for Muslims in Indonesia. Changeover after independency of Indonesia had given space to reenforce the Islamic law with Indonesianperspective, and been realized by autonomy of religious court toadjudged Islamic private cases, furthermore Islamic Law Compilation being used as referral for it. Abstraksi : Masuknya Islam ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke tujuh Masehi mempengaruhi berbagai lingkungan kehidupan Bangsa Indonesia, salah satunya dalam bidang hukum. Pengaruh Islam terhadap hukum di Indonesia mulai terasa dengan munculnya hukum Islam yang diperkenalkan dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia bersamaan dengan hukum adat pada saat itu. Kemunduran hukum Islam di Indonesia bermula ketika Belanda menerapkan teori receptie, teori ini menekan keberlakuan serta penerapan hukum Islam bagi muslim Indonesia. Perubahan yang terjadi setelah kemerdekaan memberi ruang yang cukup luas untuk kembali memberlakukan dan menerapkan hukum Islam yang bercorak ke-Indonesiaan. Keadaan ini terealisasikan oleh kemandirian Pengadilan Agama untuk memutuskan perkara yang berkaitan dengan bidang keperdataan Islam, selain itu terdapat pula KHI yang menjadi rujukannya. Keywords : Islam, Islamic law, Indonesian law. 342_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 A.Pendahuluan Islam merupakan agama yang diturunkan Allah SWT. melalui perantaran malaikat-Nya Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam perjalannya, Islam tumbuh dalam dinamika sosial kemasyarakatan hingga saat ini tumbuh menjadi agama besar di dunia. Berkembangnya ajaran Islam tidak lepas dari pengaruh kekuasaan Islam yang mengalami perluasan wilayah. Khulafa ar-Rasyidin merupakan pelopor ketercapaian hal tersebut, yang dilanjutkan oleh Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah. Perkembangan dan perluasan tersebut tidak hanya terjadi di Jazirah Arab, sebagai tempat lahirnya Islam, melainkan sampai ke wilayah Nusantara yang dikenal sekarang dengan Indonesia. Sejarahwan berpendapat bahwa masuknya Islam ke Indonesia terjadi pada awal-awal abad hijriah. Ibnu Batutah, seorang pengembara dari Maroko, menuturkan di dalam bukunya bahwa penduduk pulau-pulau yang dikunjunginya pada umumnya telah memeluk agama Islam dengan madzhab Syafi’i. Sultan Malik Dzahir Syah digambarkannya sebagai seorang pemimpin (raja/sultan) dan faqih (ahli dalam ilmu fiqih), atau seorang faqih yang raja.1 Selain itu terdapat penemuan batu nisan seorang wanita muslimah yang bernama Fatimah binti Maimun dekat Surabaya bertahun 475 H atau 1082 M. Daerah yang pertama-pertama dikunjungi ialah : 1. Pesisir Utara pulau Sumatera, yaitu di Peurlak Aceh Timur, kemudian meluas sampai bisa mendirikan kerajaan Islam pertama di Samudera Pasai, Aceh Utara. 2. Pesisir Utara pulau Jawa kemudian meluas ke Maluku yang selama beberapa abad menjadi pusat kerajaan Hindu yaitu kerajaan Maja Pahit. Bukti lain kentalnya ajaran Islam di Indonesia adalah gambaran yang diceritakan oleh Tome Pires dalam bukunya Suma Oriental bahwa terdapat satu daerah bernamakan Pase (Pasai) sebagai sebuah kota kosmopolitan, yang didiami oleh muslim beretnis Bengal. Bukti terakhir Pengaruh Agama Islam Terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia _343 muncul dari catatan sejarah Dinasti Sung dari Cina yang menyatakan bahwa telah ditemukan indikasi adanya perkampungan bangsa Arab di wilayah yang dikenal saat ini sebagai Sumatera.2 Gresik memiliki buktibukti tertua tentang adanya masyarakat muslim, dengan ditemukannya sebuah batu kubur bertuliskan Arab Khufi yang memiliki angka tahun tertua di Indonesia.3 Pedagang Timur Tengah4 merupakan pelopor Islam ke wilayah Aceh. Sejarah pun mencatat Islam berkembang di Indonesia pada Abad ke tiga belas. agama Islam berasal dari tanah Gujarat, Gowa, mayoritas dari mereka adalah para pedagang. membawa ajaran mulai masuk dan Saat itu penyebar maupun Lahore, Kerajaan Samudera Pasai pada abad ke tiga belas merupakan perintis dan pelopor kerajaan Islam di Indonesia pada saat itu, kemudian diikuti oleh Kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik, dan beberapa kerajaan lainnya.5 Aceh menjadi daerah pertama masuknya Islam ke Nusantara pada abad 1 Hijriah, dibuktikan dengan terdapatnya makam raja Samudera Pasai yang dikenal dengan Malik al-Shaleh (Malikus Shaleh) (668-1245 H/1298-1326 M).6 Pedagang-pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India pada Abad ke-7 M (H) telah melakukan aktifitas ekonomi berdagang dengan masyarakat asli Indonesia jauh sebelum ditakluknya Malaka oleh Portugis pada tahun 1511 M. Malaka pada saat itu merupakan pusat utama lalu lintas perdagangan dan pelayaran yang membawa hasil hutan dan rempah-rempah dari seluruh Nusantara ke Cina dan India. Keadaan ini menempatkan Malaka pada saat itu sebagai mata rantai pelayaran yang penting dalam penyebaran Islam di Indonesia.7 Pengaruh Islam terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia tidak dapat dinafikan keberadaannya. Munculnya nilai-nilai Islam tidak hanya mempengaruhi politik Indonesia yang mengenal partai-partai yang berbasis ajaran Islam, baik sebelum maupun setelah kemerdekaan Indonesia. Bidang ekonomi menjadi bagian lain dari akulturasi sistem ekonomi dengan Islam sebagai suatu ajaran hidup manusia, dengan 344_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 munculnya ekonomi Syariah sebagai salah satu sistem ekonomi yang berkembang di Indonesia sejak tahun 1992. Hukum menjadi bagian lain yang terpengaruh atau dipengaruhi ajaran Islam, dengan munculnya lembaga-lembaga hukum yang diatur melalui konsepsi aturan Islam, seperti wakaf, perkawinan, perceraian dan waris. Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan hukum Islam sebagai bagian dari tata hukum Indonesia, dengan menempatkan kedudukan agama menjadi rujukan untuk tercapainya tujuan negara. Tujuan ini dibentuknya Negara seperti dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-Empat, ditempuh dengan jalan melandasinya dengan satu dasar, ialah Pancasila. Satu di antaranya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, yang merupakan perwujudan diakuinya hak hidup untuk agama..8 Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari al-fiqh al-Islami, dalam istilah hukum Barat dikenal dengan Islamic Law. Dalam al-Qur’an maupun Sunnah tidak dijumpai istilah hukum Islam, yang digunakan adalah kata syari’ah yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah fiqh. Antara syariah dan fiqh memiliki hubungan yang sangat erat. Syariah tidak dapat dipahami dengan baik tanpa melalui fiqh atau pemahaman yang memadai, dan diformulasikan secara baku. Fiqh sebagai hasil usaha ijtihad, sangat dipengaruhi oleh tuntutan ruang dan waktu yang meliputi faqih (jamak fuqaha) yang memformulasikannya. Karena itulah, sangat wajar jika kemudian terdapat perbedaan dalam rumusan fikih di antara para ulama.9 Ajaran Islam mempengaruhi tata hukum di Indonesia baik hukum tertulis, maupun hukum tidak tertulis. Islam memberikan kebijaksanaan dalam menerapkan aturan ajaran Islam di dalam kehidupan bermasyarakat yaitu melalui kebijaksanaan tasyri’, taklif dan tathbiq. Kebijaksanaan tasyri’ adalah kebijaksanaan pengundangan suatu aturan hukum Allah dan Rasul-Nya sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Kebijaksanaan taklif adalah kebijaksaan dalam penerapan suatu ketentuan hukum terhadap manusia sebagai mukallaf (subjek Pengaruh Agama Islam Terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia _345 hukum) dengan melihat kepada situasi dan kondisi pribadi manusia itu; melihat kemampuan fisik, biologis dan dan rohani; mempunyai kebebasan bertindak dan mempunyai akal sehat. Kebijaksanaan tathbiq adalah kebijaksanaan perlakuan dan ketentuan hukum yang dapat saja berbeda dengan hukum perbuatan itu bagi orang lain.10 Hukum Islam bertujuan untuk memudahkan umat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Islam adalah agama yang sempurna. Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah (hablumminallah), hubungan antarsesama manusia (hablumminannas), dan hubungan manusia dengan alam (hablumminal ‘alam). Dalam hubungan itu, Allah menetapkan aturan-aturan hukum yang harus diikuti, ditaati, dan dipatuhi oleh umat Islam. Aturan hukum itu bertujuan agar manusia hidup teratur, damai, dan adil.11 Masuknya Belanda ke Indonesia mulai mempengaruhi perkembangan hukum Indonesia dengan munculnya berbagai macam hambatanhambatan yang dilakukan oleh pemerintahan Belanda, sebagai upaya untuk menekan pengaruh Islam dalam masyarakat Indonesia. Cara yang dilakukan pemerintah Belanda adalah dengan memberlakukan teori receptie, yaitu hukum yang berlaku dalam realita masyarakat adalah hukum adat, sedangkan hukum Islam dapat diberlakukan apabila telah beradaptasi dengan hukum adat, yang dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje (1857-1936), sebagai penasihat Pemerintah Belanda dalam kaitannya dengan Islam dan persoalan-persoalan pribumi. Snouck Hurgronje mendalami hukum dan agama Islam secara khusus di Indonesia, bahkan pernah melakukan penyamaran sebagai dokter mata dengan nama Abdul Ghafur di Mekkah.12 Teori ini didukung pula oleh Cornelis Van Vollenhoven (1874-1933), Bertrand Ter Haar, dan beberapa muridnya.13 Munculnya teori receptie ini memberikan argumentasi dan dasar bagi Belanda untuk membentuk sebuah komisi yang bertugas meninjau kembali wewenang Peradilan Agama di Jawa dan Madura. Dengan bekal sebuah rekomendasi dari komisi ini, lahirlah Stb (staatblad) Nomor 116 berisi pencabutan wewenang Peradilan Agama 346_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 untuk menangani masalah waris dan yang lainnya, perkara perkara ini kemudian dilimpahkan kepada Landraad (Pengadilan Negeri).14 Islam yang telah memasuki sendi-sendi kehidupan Bangsa Indonesia sejak awal abad ke satu Hijriah (tujuh Masehi) memberikan dampak yang luar biasa terhadap perkembangan hukum yang kita kenal dengan hukum Islam dalam term ke-Indonesiaan. Tulisan ini bertujuan memaparkan pengaruh Islam yang memiliki peran begitu besar terhadap perkembangan dan pembangunan hukum nasional, terutama berkaitan dengan hukum bagi muslim di Indonesia. Metode yuridis normatif dengan pendekatan historis merupakan metodelogi yang digunakan dalam tulisan ini. Yuridis normatif ditujukan untuk menganalisis bahanbahan hukum yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pendekatan historis dimaksudkan untuk memahami filosofis aturan hukum/hukum dari waktu ke waktu15 dalam ruang lingkup hukum Islam di Indonesia. B.Pembahasan 1. Islam di Indonesia Islam merupakan kata yang paling tepat digunakan sebagai ajaran Tauhid dari agama Samawi setelah munculnya agama Nasrani dan Yahudi. Kata ini merupakan refleksi dari penyerahan diri seseorang kepada Allah SWT. sebagai pencipta alam semesta. Penganut Islam disebut dengan kata sifat muslim (di negara Barat diistilahkan dengan moslem).16 Islam dalam konteks sejarah merupakan risalah yang paripurna dan universal. Islam mengatur seluruh masalah kehidupan, serta hubungan antara kehidupan itu dengan sebelum dan sesudah kehidupan. Islam juga mengatur interaksi manusia dengan penciptanya, dirinya sendiri, serta sesama manusia di setiap waktu dan tempat. Islam telah membawa corak pemikiran khas dan melahirkan sebuah peradaban yang berbeda dengan peradaban mana pun, yang mana Pengaruh Agama Islam Terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia _347 melahirkan kumpulan konsepsi kehidupan, membuat perasaan para penganutnya mendarah daging dengan corak peradabannya. Pemikiranpemikiran yang dibawa Islam juga mampu melahirkan pandangan hidup tertentu, yaitu pandangan halal dan haram, sebuah metode yang unik dalam kehidupan, serta mampu membangun sebuah masyarakat yang pemikiran, perasaan, sistem dan individu-individunya berbeda dengan masyarakat manapun.17 Islam merupakan agama dan peradaban. Fakta sejarah menggambarkan bahwa dalam jangka waktu empat belas abad sejarah manusia, Islam telah mengalami perluasan wilayah yang terbentang dari benua Asia dan Afrika, bahkan sebagian Eropa mengalami dampak dari perluasan tersebut.18 Secara umumnya kedatangan Islam di Melayu diawali abad ke7, dibawa oleh para pedagang. Hamka yang telah membuat kajian menggunakan sumber Cina dan tulisan T.W. Arnold menyebut peranan dakwah para pedagang Arab di daerah Melayu dan dunia sebelah timur adalah sekitar abad ketujuh M. Kelompok kecil pendakwah ini telah berada di daerah Melayu yaitu di bahagian barat Sumatera (674 M), dan 878 M dan di Jawa pada 1082 M, di Champa 1039 M, Semenanjung Tanah Melayu pada 878 M dan 1302 M dan semakin bertambah ramai sekitar abad ke-15. Islam telah tersebar sejak abad ke-13 atau ke-14 berdasarkan kerajaan Samudera Pasai yang merupakan kerajaan Melayu-Islam pertama.19 Ada tiga teori yang menjelaskan tentang masuknya Islam di Indonesia. Pertama, Islam telah masuk ke Indonesia ketika telah ada orang Islam di Indonesia, baik orang asing maupun orang pribumi. Kedua, Islam telah masuk ke Indonesia ketika ada orang pribumi yang telah masuk Islam. Ketiga, Islam telah ke Indonesia ketika Islam telah mengalami proses pelembagaan di wilayah Indonesia.20 Ira M. Lapidus menyatakan terdapat tiga teori yang mempengaruhi berkembangnya Islam beserta aturan-aturan yang termaktub di 348_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 dalamnya, teori pertama menekankan peran kaum pedagang yang telah melembagakan dirinya di wilayah pesisir pantai. Akulturasi yang terjadi antara penguasa lokal dan pedagang melalui lembaga pernikahan, serta kemampuan diplomatik yang dimiliki dalam perdagangan internasional merupakan faktor lain yang mempengaruhi berkembangnya Islam di daerah pesisir. Penguasa lokal merupakan kelompok pertama yang memeluk agama Islam, sebagai upaya untuk memisahkan diri kekuasaan Majapahit yang beragama Hindu, serta bertujuan untuk menarik simpati muslim untuk membentukan kelompok pedagang demi mengimbangi pedagang-pedagang Hindu di Jawa. Teori kedua, peran para sufi yang berasal dari Gujarat, Bengal, dan Jazirah Arab. Kedatangan para sufi memiliki peran tidak hanya sebagai penyebar agama Islam, melainkan pula sebagai pedagang dan politisi yang memiliki tujuan untuk menjalin komunikasi melalui perdagangan dan kekuasaan dengan penguasa lokal. Teori ketiga, berkaitan dengan penekanan akan makna Islam bagi masyarakat muslim dibandingkan makna Islam dalam pandangan penguasa lokal. Islam telah menyumbang sebuah landasan ideologis bagi kebajikan individual, bagi solidaritas kaum tani dan komunitas pedagang, dan bagi integrasi kelompok parochial yang lebih kecil menjadi masyarakat yang lebih besar.21 Ahmad Mansur Suryanegara, menjelaskan lebih lanjut tentang masuk Islam ke Indonesia berdasarkan wilayah para penyebar agama Islam: a. Teori Gujarat yang mengikuti hasil penulisan sarjana Belanda, terutama kajian dari Christian Snouck Hurgronje. Pendapatnya menyatakan bahwa Islam tidak mungkin masuk ke Indonesia secara langsung dari jazirah Arab tanpa melalui ajaran tasawwuf yang berkembang di India, terutama di daerah Gujarat dengan Kesultanan Samudera Pasai yang menerima ajaran Islam melalui jalur Gujarat ini. Ia menghubungkannya dengan penyerangan dan pendudukan Baghdad oleh Raja mongol pada Tahun 1258 M. Teori ini diperkuat oleh J. P. Moquette berdasarkan temuan arkeologis, yaitu batun nisan Sultan Malik as-Salih yang meninggal pada 669 Pengaruh Agama Islam Terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia _349 H (1297 H) di Gampong Samudera, Lhoksumawe. Data arkeologis ini dianggap sebagai batu nisan tertua yang mencantumkan sultan pertama di wilayah ini, Moquette menyimpulkan bahwa kedatangan Islam pertama di Samudera adalah pada 1270-1275 M.22 b. Teori Makkah merupakan teori yang digunakan oleh Hamka dalam menjelaskan proses masuknya Islam ke Indonesia, bahwa berdasarkan berita dari Dinasti Tang telah ditemukan permukiman pedagang Arab Islam pada abad ke 7 M di pantai barat Sumatra. Teori ini menyangkal bahwa Kesultanan Samudera Pasai yang didirikan pada 1275 M atau abad ke 13 M sebagai awal masuknya agama Islam, melainkan Kesultanan ini timbul karena perkembangan Islam pada masa itu.23 c. Teori Persia diungkap oleh Abu bakar Atjeh yang mengikuti pandangan Hoesein Djajadiningrat, bahwa islam masuk melalui jalur Persia dan bermadzhab Syi’ah. Dasar dari pendapat ini adalah bahwa sistem baca atau sistem mengeja membaca al-Qur’an, terutama di Jawa Barat mengikuti sistem Persia. Teori ini dinilai lemah karena tidak semua pengguna sistem baca huruf al-Qur’an tersebut di Persia penganut madzhab Syi’ah. d. Teori Cina merupakan pandangan yang lahir dari Slamet Muljana, yang menekankan Islam masuk ke Indonesia berdasarkan akulturasi, karena pernikahan orang pribumi Indonesia dengan orang Cina. Pendapat ini coba dibuktikan dengan lahirnya para penguasa dan ulama yang memiliki darah bangsa Cina, seperti Sultan Demak, para Wali Sanga. Pendapat ini bertolak dari Kronik Sam Po Kong.24 Berita ini diketahui melalui catatan dari Ma Huan, seorang penulis yang mengikuti perjalanan Laksamana ChengHo. Ia menyatakan melalui tulisannya bertempat tinggal di pantai utara Pulau Jawa, bahwa sejak kira-kira-kira tahun 1400 telah ada saudagar-saudagar Islam yang bertempat tinggal di pantai utara Pulai Jawa.25 350_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 e. Teori maritim N. A Baloch sejarawan Pakistan menyatakan masuk dan perkembangan agama Islam di Indonesia, akibat umat Islam memiliki kavigator atau mualim dan wirausahawan Muslim yang dinamik dalam penguasaan maritim dan pasar, melalui aktifitas ini ajaran Islam mulai dikenalkan di sepanjang jalan laut niaga di daerah pantai tempat persinggahannya pada abad ke 1 H atau abad ke 7 M.26 f. Teori Coromandel dan Malabar. Teori ini dikemukakan oleh Marrison dengan mendasarkan pada pendapat yang dipegangi oleh Thomas W. Arnold. Teori Coromandel dan Malabar yang mengatakan bahwa Islam yang berkembang di Nusantara berasal dari Coromandel dan Malabar adalah juga dengan menggunakan penyimpulan atas dasar teori mazhab. Ada persamaan mazhab yang dianut oleh umat Islam Nusantara dengan umat Islam Coromandel dan Malabar yaitu mazhab Syafi’i. Dalam pada itu menurut Marrison, ketika terjadi Islamisasi Pasai tahun 1292, Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu. Untuk itu tidak mungkin kalau asal muasal penyebaran Islam berasal dari Gujarat. g. Teori Mesir dikemukakan oleh Kaijzer ini juga mendasarkan pada teori mazhab, dengan mengatakan bahwa ada persamaan mazhab yang dianut oleh penduduk Mesir dan Nusantara, yaitu bermazhab Syafi’i. Teori Arab-Mesir ini juga dikuatkan oleh Niemann dan de Hollander. Tetapi keduanya memberikan revisi, bahwasanya bukan Mesir sebagai sumber Islam Nusantara, melainkan Hadramaut. Sementara itu dalam seminar yang diselenggarakan tahun 1969 dan 1978 tentang kedatangan Islam ke Nusantara menyimpulkan bahwasanya Islam langsung datang dari Arab, tidak melalui dan dari India.27 2. Hukum Islam di Indonesia Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang ditaati oleh mayoritas penduduk dan rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup di dalam masyarakat. Ayat al-Qur’an dan sunnah dalam al-Hadits begitu banyak Pengaruh Agama Islam Terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia _351 yang menggambarkan bahwa orang yang beriman memiliki kewajiban untuk menaati hukum. Tingkatan kehidupan beragama seorang muslim dikaitkan dengan sikap dan ketaatnya kepada Allah SWT. dan RasulNya.28 Penerapan dan pelaksanaan hukum Islam telah ada sejak permulaan abad 14 Masehi, terlihat pada masa Kerajaan Samudera Pasai sebagai kerajaan Islam pertama. Sultan Malik As-Shaleh adalah ahli dalam bidang fikih menurut madzhab Syafi’i. Dengan bantuan para ulama dari berbagai mancanegara serta dari qadhi (hakim), sultan pertama dari kerajaan ini menerapkan berbagai keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum Islam di daerahnya. Salah satu bukti penerapan dan pelaksanaan hukum Islam di Samudera Pasai dapat ditemukan dalam Prasasti Trengganu. Hukum Islam berlaku bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam karena kedudukan hukum Islam itu sendiri. Ketentuan UndangUndang Dasar Republik Indonesia 1945 telah memberi penegasan atas hal tersebut. Alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 mengungkapkan pernyataan kemerdekaan Indonesia atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Ismail Suny29 mengungkapkan bahwa sejarah hukum pada zaman Hindia Belanda mengenai hukum Islam dapat dibagi kepada dua periode: Pertama, periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya (secara kesuluruhan) yang disebut dengan receptio in complexu, yaitu periode berlakunya hukum Islam sepenuhnya bagi orang Islam karena memeluk agama Islam. Hukum Islam yang telah berlaku sejak kerajaan Islam di Nusantara hingga zaman V.O.C, yaitu hukum kekeluargaan Islam khususnya hukum perkawinan dan waris, tetap diakui oleh Belanda. Pengakuan akan teori ini dituangkan oleh V.O.C melalui peraturan Resolutie der Indische Regeering tanggal 25 Mei 1760. V.O.C memerintahkan D.W. Freijer untuk menyusun Compendium yang memuat hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk diperbaiki dan disempurnakan oleh ahli hukum Islam pada saat itu. Kitab hukum itu secara resmi 352_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 diterima oleh Pemerintahan V.O.C tahun 1706 dan dipergunakan oleh pengadilan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di kalangan umat Islam di daerah kekuasaan V.O.C. Kitab tersebut dikenal dengan dengan Compendium Freijer,30 dan kemudian menjadi dasar hukum dalam Regeering Reglemen (RR) tahun 1885. Kedua, penerimaan hukum Islam oleh hukum adat yang kemudian dikenal dengan teori receptie yaitu hukum yang berlaku dalam realita masyarakat adalah hukum adat, sedangkan hukum Islam dapat diberlakukan kalau sudah beradaptasi dengan hukum adat. Teori ini dilegalisasi dalam undang-undang dasar Himdia Belanda, sebagai pengganti RR yaitu Wet op de Staatsinrichting van Nederlands Indie (IS). Pengaruh dari perubahan RR ke IS menyebabkan dicabutnya hukum Islam dari lingkungan tata hukum Hindia Belanda melalui Staatblad No. 212 pada tahun 219. Teori ini dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje (1857-1936) dan didukung pula oleh Cornelis Van Vollenhoven (1874-1933), Bertrand Ter Haar, dan beberapa muridnya.31 Munculnya teori receptie ini memberikan argumentasi dan dasar bagi Belanda untuk membentuk sebuah komisi yang bertugas meninjau kembali wewenang Peradilan Agama di Jawa dan Madura. Dengan bekal sebuah rekomendasi dari komisi ini, lahirlah Stb (staatblad) Nomor 116 berisi pencabutan wewenang Peradilan Agama untuk menangani masalah waris dan yang lainnya. Perkara perkara ini kemudian di limpahkan kepada Landraad (Pengadilan Negeri).32 Perkembangan dan perubahan yang lebih baik dalam memaknai dan menempatkan hukum Islam di Indonesia dengan mengenyampingkan teori receptie, mulai dilakukan setelah Indonesia merdeka.33 Konstitusi pasca kemerdekaan menempatkan hukum Islam sebagai bagian masyarakat Indonesia yang tidak terpisahkan dengan ajaran Islam, karena faktor kedekatan sejarah yang membentuk Islam Indonesia, sehingga selaras dengan tujuan dari hukum Islam itu sendiri. Teori ini ditujukan untuk memberikan pengertian dan pemahaman baru akan pentingnya Islam menjadi bagian dari pembangunan hukum nasional Pengaruh Agama Islam Terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia _353 yang selaras dengan Pancasila dan UUD 1945.34 Teori ini diistilahkan dengan teori receptie exit yang dikemukan oleh Hazairin. Pokok-pokok pikiran teori ini ialah: a. Teori receptie telah patah, tidak berlaku dan exit dari tata negara Indonesia sejak tahun 1945 dengan merdekanya bangsa Indonesia dan mulai berlakunya UUD 1945. b. Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 29 ayat 1 maka negara Republik Indonesia berkewajiban, membentuk hukum nasional Indonesia yang bahannya hukum agama. Negara mempunyai kewajiban kenegaraan untuk itu. c. Hukum agama yang masuk dan menjadi hukum nasional Indonesia bukan hukum Islam saja, melainkan juga hukum agama lain untuk pemeluk agama lain. Hukum agama di bidang hukum perdata diserap dan hukum pidana diserap menjadi hukum nasional Indonesia. Itulah hukum baru Indonesia dengan dasar Pancasila.35 Perjalanan sejarah hukum Indonesia menunjukkan pula bagaimana unsur-unsur dalam sistem hukum Pancasila terisi oleh unsur-unsur hukum Islam. Pancasila terutama sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan pentingnya peran agama, atau kausa prima terhadap sila-sila lainnya dalam membangun hukum. GBHN bidang agama dengan jelas menyatakan pengaruh agama yang kuat menjadi salah satu fondasi terbentuknya hukum yang ditujukan untuk pengembangan, pembangunan, dan pembentukan hukum nasional secara keseluruhan demi kepentingan kehidupan kemasyarakatan. Ada tiga hukum Islam dalam tata kehidupan bernegara. Pertama, hukum Islam telah turut serta menciptakan tata nilai yang mengatur kehidupan umat Islam, minimal dengan menerapkan apa yang dianggap baik dan buruk, apa yang menjadi perintah, anjuran, kebolehan, dan larangan agama. Kedua, banyak keputusan hukum dan unsur yuridis prudensial dari hukum Islam telah diserap menjadi bagian dari hukum 354_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 positif yang berlaku. Ketiga, adanya golongan yang masih memiliki aspirasi teokratis di kalangan umat Islam dari berbagai negara sehingga penerapan hukum Islam secara penuh menjadi slogan perjuangan yang masih memiliki daya tarik yang besar.36 Keadaan ini menunjukkan begitu lekatnya Indonesia sebagai bangsa dan Negara dengan hukum Islam. Di satu sisi Islam memahami pentingnya proses hukum berintegrasi dengan kehidupan bermasyarakat, sisi lainnya menunjukkan proses tersebut dapat terlaksana dan dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif. Abdurrahman memberikan tiga argumentasi yang dapat menunjukkan arti penting hukum Islam bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu: a. Secara faktual umat Islam Indonesia bukan hanya sebagai kelompok mayoritas di Indonesia, melainkan menjadi mayoritas umat Islam di dunia. Keadaan ini menunjukkan hukum Islam sebagai aturan yang mengikat terhadap subjek hukum yang besar pula. Akan tetapi keadaan ini dapat dicapai sepenuhnya apabila umat Islam memperlakukan dan melaksanakan ketentuannya dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya dampak negatif terhadap kedudukan hukum Islam bila keadaan ini tidak disadari dan dilaksanakan dengan baik oleh umat Islam itu sendiri. b. Indonesia meskipun bukan merupakan negara Islam, memberikan tempat bagi hukum Islam dengan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan satu-satu asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa selaras dengan ajaran Tauhid sebagai pokok dari ajaran Islam, memberikan landasan idiil yang cukup kokoh untuk melaksanakan ketentuan hukum Islam dalam negara hukum yang berlandaskan Pancasila. Jaminan ini pula ditujukan oleh UUD 1945 dalam penghormatan akan kemerdekaan bagi masyarakat Indonesia untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Pengaruh Agama Islam Terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia _355 c. Bangsa Indonesia dan Negara Republik Indonesia dalam rangka kegiatan pembangunannya telah menempatkan Pembinaan Hukum Nasional sebagai salah satu bidang yang menjadi kajian. Hukum Islam dalam agenda kajian ini dapat menjadi salah satu bagian pokok yang sangat diperlukan untuk membina hukum Nasional tersebut. Kajian ini ditujukan untuk menunjukan bahwa hukum Islam penting menjadi pertimbangan dalam memetakan hukum nasional secara keseluruhan, karena hukum Islam berada dan berkembang bersamaan hukum adat dan lebih dahulu dibandingkan hukum Eropa Kontinental (Belanda) mempengaruhi sistem hukum Indonesia.37 Pasca kemerdekaan Indonesia dari Belanda setelah Perang Dunia ke II (dua), keterpisahan sistem hukum dalam badan peradilan menjadi bagian yang mendapatkan perhatian dari tokoh-tokoh pemimpin Indonesia pada saat itu. Tahun 1948 terdapat aturan memerintahkan peleburan Pengadilan Agama kepada Pengadilan Umum (civil courts), akan tetapi pelaksanakaannya tidak dapat dilakukan karena revolusi yang terjadi pada saat itu. Badan peradilan agama dapat terealisasikan keberadaannya pada tahun 1957, dengan mendapatkan persetujuan dari kabinet melalui peraturan pemerintah yang memberikan wewenang untuk pembentukan Pengadilan Agama di wilayah yang belum memilikinya. Aturan ini pula memberikan kewenangan untuk mendirikan Pengadilan Agama bersamaan dengan pengadilan umum yang telah ada sebelumnya, dan memiliki wilayah kewenangan absolut dan kewenangan relatif layaknya pengadilan umum.38 Kewenangan mengadili yang diberikan kepada Pengadilan Agama melalui Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957, berupa penyelesaian sengketa dalam perkawinan (perkawinan, perceraian, dan rujuk), waris, hadanah, wakaf, hibah, dan sedekah. Sebagai konsekuensi, beberapa pengadilan pribumi yang telah ada di daerah-daerah tertentu di Indonsesia melebur dan bertransformasi menjadi Pengadilan Agama. 356_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 Kedudukan Pengadilan Agama dalam sistem peradilan di Indonesia sebagai lembaga yang independen, dikuatkan dengan lahirnya UndangUndang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Undang-undang ini ditujukan untuk memberikan keleluasaan bagi Pengadilan Agama untuk melaksanakan setiap keputusan yang lahir dari persidangan, karena sebelum munculnya undang-undang ini setiap putusan yang dikeluarkan olehnya memerlukan persetujuan dan pengukuhan dari Pengadilan Umum/Pengadilan Tata Usaha Negara.39 Perubahan lain yang muncul setelah kemerdekaan adalah lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991,40 yang menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama berkaitan dengan perkawinan, waris dan harta perkawinan.41 Kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan rangkaian sejarah hukum nasional dalam mengungkapkan ragam makan kehidupan masyarakat Islam Indonesia, terutama tentang: a. Adanya norma hukum yang hidup dan ikut serta bahkan mengatur interaksi sosial. b. Aktualnya dimensi normatif akibat terjadinya eksplanasi fungsional ajaran Islam yang mendorong terpenuhinya tuntutan kebutuhan hukum. c. Alim ulama Indonesia mengantisipasi ketiga hal di atas dengan kesepakatan bahwa KHI adalah rumusan tertulis hukum Islam yang hidup seiring dengan kondisi hukum dan masyarakat Indonesia.42 Pada peradilan agama sendiri, terdapat 13 buah kitab fikih bermazhab Syafi’i sebagai sumber hukum materiil untuk menyelesaikan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama.43 Keanekaragaman kitab fikih sebagai sumber hukum untuk memutuskan perkara di Pengadilan Agama berimplikasi terhadap kemungkinan terjadinya perbedaan putusan atau disparitas antar Pengadilan Agama satu wilayah dengan Pengaruh Agama Islam Terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia _357 wilayah lainnya untuk perkara yang sama. Keadaan inilah yang menjadi salah satu alasan untuk dilakukannya unifikasi hukum Islam khususnya di bidang hukum keluarga. Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku mencoba menjawab permasalahan ini. KHI disusun dan dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum substansial pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Pemberlakuan KHI memberikan tempat secara yuridis bahwa hukum Islam di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan menjadi hukum positif tertulis dalam sistem hukum nasional (tata hukum Indonesia). Ia menjadi dasar untuk pengambilan keputusan hukum terhadap perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.44 Bagi mereka yang berperkara di Pengadilan Agama, dapat melakukan pembelaan dan segala upaya untuk mempertahankan hak dan kewajibannya dengan tidak boleh menyimpang dari kaidah Kompilasi Hukum Islam. KHI memberikan acuan pada proses persidangan bahwa para pihak tidak boleh mempertentangkan pendapat-pendapat yang terdapat dalam kitab fiqih tertentu. Begitu pula dengan penasihat hukum, mereka hanya diperkenankan mengajukan tafsir dengan bertitik tolak dari rumusan Kompilasi Hukum Islam. Semua pihak yang terlibat dalam proses di Peradilan Agama, sama-sama mencari sumber dari muara yang sama yaitu Kompilasi Hukum Islam.45 KHI menjadi penting sebagai rujukan dan landasan putusan Peradilan Agama. KHI merupakan suatu perwujudan hukum Islam yang khas Indonesia, pandangan ini dapat dilihat dari unsur-unsur sistem hukum nasional:46 a. Landasan ideal dan konstitusi KHI adalah Pancasila dan UndangUndang Dasar 1956. Ketentuan ini dimuat dalam konsideran Instruksi Presiden dan dalam Penjelasan Umum Kompilasi Hukum Islam yang disusun sebagai bagian dari sistem hukum nasional dan menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan 358_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran masyarakat dan bangsa Indonesia. b. KHI dilegalisasi oleh isntrumen hukum dalam bentuk Instruksi Presiden yang dilaksanakan oleh Keputusan Menteri Agama, dan merupakan bagian dari rangkaian peraturan perundangundangan yang berlaku. Instruksi Presiden ini tidak mengurangi sifat legalitas dan otoritasnya, dikarenakan segala yang dirumuskan di dalamnya merupakan suatu kebutuhan akan ketertiban masyarakat Islam masa kini dan masa yang akan datang. Kandungan isi dari KHI disusun dan diupayakan berdasarkan keinginan dan kesadaran masyarakat yang membutuhkannya. c. KHI dirumuskan dengan merujuk pada sumber hkum Islam, yaitu al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. yang bercorak keIndonesiaan. d. Aktualisasi KHI berada pada wewenang badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama, berdasarkan tafsiran teologis dari penjelasanya. Bidang kewarisan (Buku II) pola dasarnya merupakan peralihan bentuk dari kewarisan menurut pada fuqaha (dalam lingkungan “tradisi besar” meminjam istilah redfield ke dalam bentuk kanun (qanun). C.Penutup Pengaruh Islam terhadap hukum di Indonesia mulai terasa dengan munculnya Hukum Islam sebagai suatu sistem yang bermula dan dimulai pada saat datangnya para cendekiawan dan pedagang muslim ke Indonesia. Melalui peran keduanya Islam dapat tumbuh dan berkembang. Hukum Islam mulai diperkenalkan dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat pada saat itu bersamaan dengan hukum adat yang telah ada jauh sebelum masuknya Islam. Pengaruh hukum Islam mulai berkurang ketika masuknya Belanda dan menerapkan teori receptie. Teori ini menekan keberlakuan serta Pengaruh Agama Islam Terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia _359 penerapan hukum Islam bagi muslim Indonesia. Namun perubahan yang terjadi setelah kemerdekaan memberi ruang yang cukup luas bagi muslim Indonesia untuk kembali memberlakukan dan menerapkan hukum Islam yang bercorak ke-Indonesiaan. Keadaan ini terealisasikan oleh kemandirian Pengadilan Agama untuk memutuskan perkara yang berkaitan dengan bidang keperdataan Islam, selain itu terdapat pula KHI sebagai rujukan memeriksa dan memutuskan di Pengadilan Agama. 360_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 Daftar Pustaka Abdul Halim, “Membangun Teori Politik Hukum Islam Di Indonesia”, dalam Jurnal Ahkam, 2013, Vol. XIII, No. 2, Juli. Ali Imron, “Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional (Studi Tentang Konsepsi Taklif dan Mas`uliyyat dalam Legislasi Hukum)”, dalam Disertasi pada, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2008. Ahmad, Amarullah, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Gema Insani Press, 1996. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992. A. Hasymi, (ed.), Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia, Bandung: Al-Ma’arif, 1989. Arba’iyah Mohd Noor, “Perkembangan Pensejarahan Islam Di Alam Melayu”, dalam Jurnal Al-Tamaddun, 2011, Bil. 6. Azizy, A. Qadri, Eklektisisme Hukum Nasional, Yogyakarta: Gama Media, 2002. Darmawijaya, Kesultanan Islam Nusantara, Jakarta: al-Kautsar, 2010. Djajadiningrat, P.A. Hoesain, Tinjauan Kritis Tentang Sejarah Banten, Jakarta: Pustaka Jaya, 1983. Edyar, Busman dkk (ed.), Sejarah Peradaban Islam, Jakarta: Pustaka Asatruss, 2009. Gani Abdullah, Abdul, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Gema Insani Press, 1994. H. A. R. Gibb, Islam dalam Lintasan Sedjarah, Djakarta: Bhratara, edisi terj. 1960. Pengaruh Agama Islam Terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia _361 Hamid, Zahri, Prinsip-Prinsip Hukum Islam tentang Pembangunan Nasional di Indonesia, Yogyakarta: Bina Cipta, 1975. Habib Muhsin Syafingi, “Internalisasi Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Peraturan Daerah “Syari’ah” di Indonesia”, dalam Jurnal Pandecta, 2012, Vol. 7, No. 2, Juli. Hamka, Sejarah Umat Islam IV, Jakarta: Bulan Bintang, 1961. Hossein Nasr, Seyyed, Islam Religion, History, and Civilization, New York: HarperSan Fransisco, 2003. Husein Nasution, Amien, Hukum Kewarisan (Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam), Jakarta: Rajawali Pers, 2012. Ichtijanto, Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia, dalam Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukannya, Bandung: Rosdakarya, 1991. Idri, “Religious Court in Indonesia History and Prospect”, dalam Journal Of Indonesian Islam, 2009, Vol. 03, No. 02, December. Karim, Muchith A., (editor), Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia, , Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, Badan Litbang dan Pustlitbang Kehidupan Keagamaan, 2010. Lapidus, Ira M., Sejarah Sosial Umat 1 & 2, Jakarta: Rajawali Pers, 1999. Mahmud Marzuki dan Peter, Metodelogi Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2013. Mardani, “Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional”, dalam Jurnal Hukum, 2009, No. 2 Vol. 16 April. ----------, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2014. Manan, Abdul, Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006. Mansur Suryanegara, Ahmad, Api Sejarah, Bandung: Salamadani Pustaka 362_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 Semesta, 2009. Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. M. B. Hooker, Islam in South-East Asia, Leiden: E. J. Brill, 1983. -----------------, “Introduction: Islamic Law in South-east Asia”, dalam Asian Law Journal, 2002, Vol.4. M. Karsayuda, Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Total Media, 2006. Mark E. Cammack and R. Michael Feener, “The Islamic Legal System In Indonesia”, dalam Pacific Rim Law & Policy Journal, 2012, Vol. 21 No. 1, January. Muhammad Daud Ali, dkk, Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Cik Hasan Bisri ed), Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999. Muhammad Julijanto, “Implementasi Hukum Islam Di Indonesia Sebuah Perjuangan Politik Konstitusionalisme”, dalam Conference Proceedings of Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII), UIN Sunan Ampel Surabaya, t.th. Muarif Ambary, Hasan, Sejarah Perkembangan Islam di Indonesia, dalam Kebangkitan Islam dalam Pembahasan, Bandung: Yayasan Nurul Islam, t.th. Oksep Adhayanto, “Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam”, dalam Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, 2011, Vol. 1, No. 1. Praja, Juhaya S., Pengantar, dalam Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukannya, Bandung: Rosdakarya, 1991. Rafiq, Ahmad, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta: Gama Widya, 2001. Ramulto, Moh. Idris, Asas-Asas Hukum Islam (Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedududukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Pengaruh Agama Islam Terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia _363 Indonesia), Jakarta: Sinar Grafika, 1995. Samsul Wahidin, Abdurrahman, Perkembangan Ringkas Hukum Islam di Indonesia, , Jakarta: Akademika Pressindo, 1984. Samsul Wahidin, Abdurrahman, Perkembangan Ringkas Hukum Islam di Indonesia, , Jakarta: Akademika Pressindo, 1984. Suny, Ismail, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, dalam Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukannya, Bandung: Rosdakarya, 1991. Syamsul Bahri, “Pelaksanaan Syari’at Islam Di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”, dalam Jurnal Dinamika Hukum, 2012, Vol. 12, No. 2, Mei. Tandrasasmita, Uka, Arkeologi Islam Nusantara, Jakarta: KPG, 2009. Thalib, Sayuti, Receptio in Complexu, Theorie Receptie dan Receptio A Contrario, dalam Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1976. Yatim, Badri, Sejarah Peradaban Islam (Dirasah Islamiyah II), Jakarta: Rajawali Pers, 2011. Yulkarnain Harahab dan Andy Omara, “Kompilasi Hukum Islam Dalam Perpektif Hukum Perundang-Undangan”, dalam Jurnal Mimbar Hukum, 2010, Volume 22, Nomor 3, Oktober. Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 1983. 364_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 Endnotes 1. Amarullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, h. 55. 2. M. B. Hooker, Islam in South-East Asia, Leiden: E. J. Brill, 1983, h. 4. 3. Hasan Muarif Ambary, Sejarah Perkembangan Islam di Indonesia, dalam Kebangkitan Islam dalam Pembahasan, Bandung: Yayasan Nurul Islam, t.th, h. 63. 4. Pedagang Arab Telah datang ke Indonesia sejak masa kerajaan Sriwijaya (abad ke-7 M) yang menguasai jalur pelayaran perdagangan di wilayah Indonesia bagian barat termasuk Selat Malaka pada waktu itu. Hubungan pedagang Arab dengan kerajaan Sriwijaya terbukti dengan adanya para pedagang Arab untuk kerajaan Sriwijaya dengan sebutan Zabak, Zabay atau Sribusa. Pendapat ini dikemukakan oleh Crawford, Keyzer, Nieman, de Hollander, Syekh Muhammad Naquib Al-Attas dalam bukunya yang berjudul Islam dalam Sejarah Kebudayaan Melayu dan mayoritas tokoh-tokoh Islam di Indonesia seperti Hamka dan Abdullah bin Nuh. Bahkan Hamka menuduh bahwa teori yang mengatakan Islam datang dari India adalah sebagai sebuah bentuk propaganda, bahwa Islam yang datang ke Asia Tenggara itu tidak murni. Busman Edyar, dkk (ed.), Sejarah Peradaban Islam, Jakarta: Pustaka Asatruss, 2009, h. 207. 5. Amien Husein Nasution, Hukum Kewarisan (Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam), Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h. 2. 6. Syamsul Bahri, “Pelaksanaan Syari’at Islam Di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”, dalam Jurnal Dinamika Hukum, Mei 2012, Vol. 12 No. 2. h. 360. Masuknya Islam membawa perubahan dalam masyarakat Aceh. Nilai-nilai Islam mulai diaplikasikan dan diterapkan dalam kehidupan masyarakatnya yang sebelumnya beragama Hindu. Penerapan syari’at Islam mulai ada dan berkembang pada kerajaan-kerajaan Aceh, hingga puncaknya pada kesultanan Iskandar Pengaruh Agama Islam Terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia _365 Muda (1607-1636 M). Hukum Islam mulai mengalami perkembangan dengan berakulturasi dengan masyarakat Indonesia diawali mulai dari Aceh dengan berkembangan Hukum Islam pada masa Iskandar Muda yang menerapkan secara kaffah (menyeluruh) aturan-aturan Islam dengan masdzhab Syafi’i yang meliputi bidang ibadah, ahwal as-syakhshiyyah (hukum keluarga), jinayah (pidana Islam), uqubah (hukuman), murafa’ah, iqtishadiyyah (peradilan), dusturiyyah (perundang-undangan), akhlaqiyyah (moralitas), dan ‘alaqah dauliyyah (kenegaraan). 7. Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam (Dirasah Islamiyah II), Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 191-192. 8. Samsul Wahidin, Abdurrahman, Perkembangan Ringkas Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Akademika Pressindo, 1984, h. 97. 9. Muhammad Julijanto, “Implementasi Hukum Islam Di Indonesia Sebuah Perjuangan Politik Konstitusionalisme”, dalam Conference Proceedings of Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII), Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, t.th. h. 669. Hukum Islam pada hakekatnya meliputi hukum Aqidah (keyakinan tentang ad-Din), Hukum-hukum Akhlaq, Hukum-hukum Amaliyah yang meliputi aspek-aspek: peribadatan, mukallaf, pergaulan, kehartaan, perkawinan, kewarisan, perekonomian, ketatanegaraan, kemasyarakatan, kepidanaan, peradilan, hubungan antar golongan dan hubungan internasional. Zahri Hamid, Prinsip-Prinsip Hukum Islam tentang Pembangunan Nasional di Indonesia, Yogyakarta : Bina Cipta, 1975, h. 36. 10. Ali Imron, Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional (Studi Tentang Konsepsi Taklif dan Mas`uliyyat dalam Legislasi Hukum), Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, h. 57, tidak dipublikasikan. Bahtiar Effendy menulis bagaimana ciri Islam yang paling menonjol dapat diterima dalam berbagai keadaan maupun kondisi yang dapat mempengaruhi pada setiap sistem hukum, yaitu sifatnya yang “hadir di mana-mana (omnipresence)”. Ini sebuah pandangan yang mengakui bahwa di mana kehadiran Islam selalu memberikan “panduan moral yang benar bagi tindakan manusia”. Hal tersebut ditandaskan oleh Muhammad Hisyam, bahwa karakter Islam yang tidak terbatas pada domain kepercayaan, ritual, dan moral, tetapi 366_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 juga meliputi penataan masyarakat. Muhammad Julijanto, “Implementasi Hukum Islam Di Indonesia Sebuah Perjuangan Politik Konstitusionalisme”, dalam Conference Proceedings of Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII), Surabaya: UIN Sunan Ampel, t.th. h. 667. 11. Habib Muhsin Syafingi, “Internalisasi Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Peraturan Daerah “Syari’ah” di Indonesia”, dalam Jurnal Pandecta, 2012, Volume 7. Nomor 2. Juli, h. 141. 12. Moh. Idris Ramulto, Asas-Asas Hukum Islam (Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedududukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia), Jakarta: Sinar Grafika, 1995, h. 56. 13. Abdul Manan, Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006, h. 11. Klaim provokatif dan distorsif ini sangat berpengaruh terhada eksistensi hukum Islam ketika itu, bahkan hingga sekarang ini, sampaisampai Hazairin menyebutnya sebagai teori “iblis”. Ahmad Rafiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta: Gama Widya, 2001, h. 68. 14. A. Qadri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional, Yogyakarta: Gama Media, 2002, h. 155. 15. Peter Mahmud Marzuki, Metodelogi Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2013, h. 166. 16. H. A. R. Gibb, Islam dalam Lintasan Sedjarah, Djakarta: Bhratara, 1960, edisi terj. h. 9. 17. Oksep Adhayanto, “Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam”, dalam Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, 2011, Vol. 1, No. 1, h. 80. al-Qur’an pada dasarnya adalah kitab yang memuat pesan-pesan, petunjuk-petunjuk, dan perintah moral bagi kepentingan hidup manusia di muka bumi. Petunjuk dan perintah ini bercorak universal, abadi, dan fungsional, sebagai intisari wahyu terakhir. 18. Seyyed Hossein Nasr, Islam Religion, History, and Civilization, New York: HarperSan Fransisco, 2003, h. xi. 19. Arba’iyah Mohd Noor, “Perkembangan Pensejarahan Islam Di Alam Melayu”, dalam Jurnal Al-Tamaddun, Bil. 6, 2011, h. 30. 20. Darmawijaya, Kesultanan Islam Nusantara, al-Kautsar, Jakarta: t.p. 2010, Pengaruh Agama Islam Terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia _367 h. Xi. 21. Ira M. Lapidus, Sejarah Sosial Umat 1 & 2, Jakarta: Rajawali Pers, 1999, h. 718-719. 22. Uka Tjandrasasmita, Arkeologi Islam Nusantara, Jakarta: KPG, 2009, h. 13. Ahli tasawuf hidup dalam kesederhanaan, mereka selalu berusaha menghayati kehidupan masyarakatnya dan hidup bersama di tengahtengah masyarakatnya. Para ahli tasawuf biasanya memiliki keahlian untuk menyembuhkan penyakit dan lain-lain. Jalur tasawuf, yaitu proses islamisasi dengan mengajarknan teosofi dengan mengakomodir nilai-nilai budaya bahkan ajaran agama yang ada yaitu agama Hindu ke dalam ajaran Islam, dengan tentu saja terlebih dahulu dikodifikasikan dengan nilai-nilai Islam sehingga mudah dimengerti dan diterima. Busman Edyar, dkk (ed.), Sejarah Peradaban Islam, Jakarta: Pustaka Asatruss, 2009, h. 208. 23. Teori ini selain Hamka dikedepankan oleh W. P. Grooeneveldt, T. W. Arnold, Syed Naguib al-Attas, George Fadlo Hourani, J. C. van Leur, Uka Tjandrasasmita. Kedatangan Islam sejak abad 7 dan 8 M dipicu oleh perkembangan hubungan dagang laut nusantara bagian timur dan barat Asia, terutama setelah kemunculan dan perkembangan tiga dinasti kuat, yaitu, Kekhalifahan Umayyah (660-749 M) di Asia Barat, Dinasti Tang (618907 M) di Asia Timur dan Kerajaan Sriwijaya (7-14 M), di Asia Tenggara. Uka Tandrasasmita, Arkeologi Islam Nusantara, Jakarta: KPG, 2009, h. 12-13. 24. Misalnya Soeltan Panembahan Demak Fatah dalam Kronik Sam Po Kong bernama Panembahan Jin Bun. Arya Damar sebagai pengasuh Panembahan Jin Bun pada saat di Palembang bernama Swan Liong. Sultan Treggana memiliki nama Cina Tung Ka Lo. Wali Sanga yang memiliki nama Cina antara lain Soenan Ampel (Bong Swi Hoo), Soenan Goenoeng Djati (Toh A Bo). G. W. J. Drewes menyatakan bahwa teori ini lemah karena kurangnya data dan sitem interpretasi yang kurang tepat, akibat pengambilan data yang dikumpulkan tidak tepat dan tidak beralasan. 25. Teori ini dikemukakan oleh Emanuel Godinho de Eradie seorang scientist Spanyol. (Anonim). 26. Ahmad Mansur Suryanegara, Api Sejarah, Bandung: Salamadani Pustaka Semesta, 2009, h. 99-102. 368_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 27. A. Hasymi, (ed.). Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia, Bandung: Al-Ma’arif, 1989, h. 7. 28. Ichtijanto, Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia, dalam Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukannya, Bandung: Rosdakarya, 1991, h. 100. 29. Ismail Suny, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, dalam Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukannya, Bandung: Rosdakarya, 1991, h. 73-75. Teori ini dicetuskan oleh pakar hukum Belanda bernama Lodewijk Willem Christian van den Berg. 30. Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 140. 31. Abdul Manan, Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006, h. 11. 32. A. Qadri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional, Yogyakarta: Gama Media, 2002, h. 155. Ismail Suny mengungkapkan reaksi pihak Islam terhadap campur tangan Belanda dalam masalah hukum Islam ini banyak ditulis dalam buku-buku dan surat kabar-surat kabar pada saat itu. Tujuan politik hukum Belanda ini ditujukan untuk memperkuat kepentingan kekuasaannya di Indonesia, oleh karena itu tatkala kesempatan terbuka pada saat BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) terbentuk dan bersidang pada zaman penjajahan Jepang, pemimpin-pemimpin Islam memperjuangkan berlakunya hukum Islam dengan kekuaatan Islam tanpa dihubungkan dengan hukum adat. 33. Hukum Islam pada zaman kemerdekaan pun mengalami dua periode: Pertama, perode penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif dalam hukum konstitusi dimaknai sebagai sumber hukum yang baru diterima orang apabila ia telah diyakini. Dalam konteks hukum Islam Piagam Jakarta sebagai salah satu hasil dari sidang BPUPKI merupakn persuasive source bagi grondwet-interpretatie dari UUD 1945 selama empat belas tahun (Sejak 22 Juni 1945 ketika ditandatangani gentlemen agreement antara pemimpin nasionalis Islam dengan nasionalis sekuler sampai 5 Juli 1959, sebelum Dekrit Presiden RI diundangkan). Hukum Islam menjadi sumber autoritatif dalam hukum tata negara ketika ditempatkannya Piagaman Jakarta dalam Pengaruh Agama Islam Terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia _369 Dekrit Presiden RI 5 Juli 1959. Juhaya S. Praja, Pengantar, dalam Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukannya, Bandung: Rosdakarya, 1991, h. Xi. 34. Di Indonesia, Syariat Islam dan negara adalah dua entitas yang sepanjang sejarah Indonesia senantiasa terlibat pergumulan dan ketegangan abadi dalam memosisikan relasi agama (syariat Islam) dan negara, antara proyek sekularisasi dan Islamisasi negara dan masyarakat. Ketegangan ini terjadi dalam dua tataran penting yang berbeda. Pertama, tataran scholastik atau bersifat teoritik-idealistik. Perdebatan ini mencuat ke permukaan pada akhir tahun 1930-an antara Sukarno dan Mohammad Natsir. Kedua, tataran realisticpolitik atau ideologis-empirik. Polemik ini terjadi ketika merumuskan dasar konstitusi negara Indonesia modern pasca-kolonial yang berlangsung dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), 28 Mei-1 Juni 1945 dan 10-17 Juli 1945, dan dalam sidang-sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 18 sampai 22 Agustus 1945, dalam rangka penyusunan dan pengesahan UUD 1945. Abdul Halim, “Membangun Teori Politik Hukum Islam Di Indonesia”, dalam Jurnal Ahkam, Juli 2013, Vol. XIII, No. 2, h. 260. 35. Mardani, “Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional”, dalam Jurnal Hukum, 2009, No. 2 Vol. 16 April, h. 269. Seorang tokoh lain yang juga menentang teori receptie adalah Sayuti Thalib yang menulis buku Receptie a Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam. Teori ini mengandung sebuah pemikiran bahwa, hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Melalui teori ini jiwa pembukaan dan UUD 1945 telah mengalahkan Pasal 134 ayat 2 Indische Staatsregling itu. 36. Juhaya S. Praja, Pengantar, dalam Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukannya, Bandung: Rosdakarya, 1991, h. xiv-xv. 37. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, h. 2-4. 38. Mark E. Cammack and R. Michael Feener, “The Islamic Legal System In Indonesia”, dalam Pacific Rim Law & Policy Journal, 2012, Vol. 21, No. 1, January, h. 16-17. Keinginan untuk mendirikan pengadilan agama yang mandiri terpisah dari badan peradilan lain tampak mulai tahun 1951 dengan adanya aturan pada saat itu yang menyatakan akan dibentuk pengadilan 370_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 agama melalui peraturan pemerintah. Aturan ini pula yang menjadi dasar bagi lahirnya peraturan pemerintah tahun 1957 dalam pembentukan Pengadilan Agamadi seluruh Indonesia. 39. Idri, Religious Court in Indonesia History and Prospect, dalam Journal Of Indonesian Islam, 2009, Vol. 03, No. 02, December, h. 309-310. UndangUndang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Undang-undang ini mengalami perluasan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa yang berdasarkan prinsip Islam. Kewenangan tersebut antara lain: pengawasan, penyelesaian sengketa di tingkat pertama terhadap orang Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah dan tansaksi ekonomi syari’ah (bank syari’ah, lembaga keuangan mikro, asuransi syari’ah, reasuransi syari’ah, shari’ah mutual funds, saham syari’ah, shari`ah securities medium term, sekuritas syari’ah, pembiayaan syari’ah, shari`ah mortgage, dan binis berbasis syari’ah. 40. Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, h. 62. 41. MB. Hooker, “Introduction: Islamic Law in South-east Asia”, dalam Asian Law Journal, 2002, Vol.4, h. 221. 42. Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, h. 62. 43. lihat Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958 Nomor B/I/735. 44. Yulkarnain Harahab, “Andy Omara, Kompilasi Hukum Islam Dalam Perpektif Hukum Perundang-Undangan”, dalam Jurnal Mimbar Hukum, 2010, Vol. 22, No. 3, Oktober, h. 627. 45. M. Karsayuda, Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam, , Yogyakarta: Total Media, 2006, h. 103. 46. Muchith A. Karim (editor), Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia, , Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, Badan Litbang dan Pustlitbang Kehidupan Keagamaan, 2010, h. 4-5. Prinsip-prinsip Keadilan Wanita dalam Islam: Sebuah Kajian Pra-nikah _371 Principles of Justice Women in Islam: A Study of Pre-marriage Prinsip-prinsip Keadilan Wanita dalam Islam: Sebuah Kajian Pra-nikah Ru’fah Abdullah Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Maulana Hasanuddin Banten email: [email protected] Tata Setiana Indonesia Youth Forum email : [email protected] Abstract : The universality of Islamic teachings wrote clearly in the texts of the Qur’an and prophetic narrations. Best explanation of the universal message of Islam brought by one of them lies in the amount of attention devoted to the individual human being, on the principles of justice. One of the principles of justice which is responsible for individual rights in Islam are systematically and widely summarized in the theme of marriage. The importance of the theme of marriage (munakahat) addresses the potential equality between the rights earned by men and women to be the main study of Islamic law, beside the three other major discussion of such worship, muamalah and jinayah. In the theme of marriage, the principles of justice as if just found after the bound between pairs of men and women in the event of a valid contract. It illustrates the multiple phases before it happen or in pre-marital principles of justice have not becoming a focus discussion in the study of Islamic law. Regarding the latest perspective, we should bear this paper to the study of pre-marital to explore the principles of justice, especially what to receive by the lady in entering the realm of marriage. Abstraksi : Universalitas ajaran Islam termaktub secara jelas dalam nash-nash al-Qur’an dan riwayat-riwayat kenabian. Pengutaraan terbaik dari pesan universal yang dibawa oleh Islam salah satunnya terletak pada perhatian besarnya yang ditujukan kepada individu manusia, tentang prinsip-prinsip keadilan. Salah satu prinsip keadilan yang menaungi hak-hak individu dalam Islam secara sistematis dan luas terangkum 372_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 dalam tema perkawinan. Pentingnya tema perkawinan (munakahat) yang membahas potensi kesetaraan antara hak-hak yang diterima oleh laki-laki dan wanita menjadi kajian utama hukum Islam, selain tiga pembahasan utama lainnya seperti ibadah, muamalah dan jinayah. Dalam tema perkawinan, prinsip keadilan seakan baru ditemukan pasca terikatnya antara pasangan laki-laki dan wanita dalam peristiwa akad yang sah. Hal ini menggambarkan bahwa beberapa fase sebelum itu atau di masa pra-nikah prinsip-prinsip keadilan belum menjadi fokus pembahasan dalam kajian hukum Islam. Berkenaan dengan perspektif terakhir tersebut, perlu kiranya tulisan ini diarahkan kepada kajian pra-nikah yang menelusuri prinsip-prinsip keadilan khususnya yang diterima oleh pihak wanita menjelang memasuki ranah perkawinan. Keywords: Women, Pre-marital, Justice. A.Pendahuluan Isu kesetaraan antara laki-laki masih menjadi pembahasan yang aktual di kalangan sarjana muslim. Hal ini tak lepas dari berbagai isu yang terus menggelinding seiring dengan laju modernitas dan problematika di dalamnya. Sebagai sebuah pemikiran, tentunya diskursus kesetaraan ini akan terus berjalan seiring dengan berkembanganya wawasan dan dinamika sosial kemasyarakatan. Para sarjana mensinyalir, agama sering dituduh sebagai sumber terjadinya ketidakadilan dalam masyarakat, termasuk ketidakadilan relasi antara laki-laki dan perempuan dengan hilangnya kesetaraan antara keduanya. Hal ini tak lepas dari teks agama yang sering menjadi rujukan. Isu kesetaraan muncul ketika disadari bahwa perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan telah melahirkan ketidakadilan dalam berbagai bentuk seperti marginalisasi atau pemiskinan ekonomi, subordinate atau anggapan tidak penting dalam urusan politik, stereotype atau pencitraan yang negatif bagi perempuan. Citra perempuan yang dimaksud hanya bergelut pada 3R (dapur, sumur,kasur), kekerasan, dan double burden (beban ganda) terhadap perempuan yang bermuara pada perbuatan tidak adil yang dibenci oleh Allah SWT.1 Prinsip-prinsip Keadilan Wanita dalam Islam: Sebuah Kajian Pra-nikah _373 Hakikatnya, Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan persamaan mengandung prinsip-prinsip kesetaraan. Dalam teks alQur’an maupun hadits, dua sumber primer hukum Islam, ditegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba, khalifah di bumi, dan menerima perjanjian primordial. Pada saat bersamaan, keduanya memiliki potensi yang sama dalam meraih prestasi optimal, yaitu derajat takwa di hadapan Allah SWT.2 Dalam al-Qur’an pengakuan tentang adanya perbedaan (distinction) antara laki-laki dan Wanita tidak serta merta mendukung atas terjadinya pembedaan (discrimination), yang dapat menyebabkan keuntungan di satu pihak serta kerugian di pihak yang lain.Nasaruddin Umar dalam penelitiannya menyebutkan, adanya perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung obsesi al-Qur’an, yaitu terciptanya hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang (mawaddah wa rahmah) di lingkungan keluarga, (QS. al-Rûm/30:21) sebagai cikal bakal terwujudnya komunitas ideal dalam suatu negeri yang damai penuh ampunan Tuhan (baldat-un thayyibat-un wa rabb-un ghafur(QS. Saba/34:15).3 Nasaruddin menambahkan, dalam al-Qur’an terdapat ayat-ayat menjelaskan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, diantaranya: laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial (QS. al-A’raf/7: 172); Adam dan Hawa sama-sama terlibat dalam drama kosmis (QS.al-Baqarah/2: 35, 187, QS.al-A’raf/7: 20, 22, 23); laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan untuk meraih prestasi (QS. Ali Imran/3: 195), laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di muka bumi (QS. AlAn’am/6: 165, QS. Al-Nisa/4: 124, QS.al-Nahl/16: 97, QS. Ghafir/40: 40), laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba (QS.al-Dzariat/51: 56).4 Sedangkan konsekuensi atas tidak adanya status pembedaan antara laki-laki dan wanita di dalam al-Qur’an, menunjukkan pesan universalisme Islam dalam menghargai hak-hak asasi, yang secara alamiah telah dinisbahkan bagi keduanya sebagai makhluk utama sang pencipta. Berkaca dari semangat universalismenya tersebut, Islam tidak 374_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 saja memberikan bukti bahwa kajian hukum kontemporer tentang HAM, tidak lagi melulu menjadi monopoli kampanye dari pihak negara-negara barat saja. Melainkan secara jelas dalam jejak nash dan riwayat kenabian, penghargaan atas hak kesetaraan merupakan ikhtiar kelanggengan dari ajaran rahmatan lil alamin dalam islam, Ajaran al-Qur’an tentang status kesetaraan antara laki-laki dan wanita dalam beberapa derajat penilaiannya di hadapan Allah, salah satunya tercantum di dalam Al-Ahzab ayat 35: Artinya:“Sesungguhnya laki-laki dan wanita muslim, laki-laki dan wanita mukmin, laki-laki dan wanita yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan wanita yang benar, laki-laki dan wanita yang sabar, laki-laki dan wanita yang khusuk, laki-laki dan wanita yang bersedekah, laki-laki dan wanita yang berpuasa, lakilaki dan wanita memelihara kehormatannya, laki-laki dan wanita yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar” (QS. Al-ahzab/33:35) Dalam keterangan lain, al-Qur’an menyebutkan tentang kapasitas laki-laki dan wanita sebagai satu-satunya pewaris bagi keberlangsungan hidup manusia yang senantiasa setara, serta saling silih melengkapi atas kebutuhan masing-masing mereka. Bentuk hubungan yang saling membutuhkan itu, ditamsilkan sebagai pakaian yang saling menutupi tubuh satu pihak, dan satu tubuh pihak lainnya.Sebagaiamana didalam QS. Al-Baqarah/2: 187: Prinsip-prinsip Keadilan Wanita dalam Islam: Sebuah Kajian Pra-nikah _375 Artinya:“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu” (QS. al-Baqarah/2: 187) Berkiblat kepada prinsip-prinsip kesetaraan antara pasangan bani adam seperti yang telah dinormakan oleh nash al-Qur’an di atas, menunjukkan pesan utama ajaran Islam tentang keadilan. Syahdan, jika ditemukan nilai ajaran Islam yang tidak mengedepankan prinsip keadilan khususnya dalam konteks relasi antar individu manusia atau kemasyarakatan maka dapat dipastikan bahwa pemahaman tersebut sangat layak untuk dipersoalkan. B.Pinsip Kesetaraan dan Keadilan dalam Islam Konteks normatif tentang prinsip keadilan yang dipesankan oleh alQur’an dapat digali, salah satunya dalam tema perkawinan. Penelusuran atas prinsip keadilan di dalam perkawinan saat ini dinilai cukup mendesak dan diperlukan, seiring dengan semakin berkembangnya pola perubahan sosial yang terjadi dalam level masyarakat, terutama yang memengaruhi lingkungan keluarga. Kesadaran masing-masing individu seorang muslim, baik itu lakilaki maupun wanita dalam memahami pesan keadilan seperti yang diwartakan oleh al-Qur’an, khususnya pada fase perkawinan dituntut untuk lebih ditingkatkan. Hal ini sangat dibutuhkan demi mewujudkan hakikat perkawinan yang berkeadilan dan ideal. Sedangkan pada tataran yang lain kekuatan pemahaman seorang muslim dalam ikhtiarnya menuju idealitas perkawinan perlu diimbangi pula oleh asas pemahaman konstitusional. Pada konteks perkawinan jaminan atas nilai keadilan dan kesetaraan hak antara laki-laki (suami) dan wanita(istri) tertuang secara lugas dalam penjelasan pasal 6 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi: 376_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 “Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.”5 Berdasarkan penjelasan pasal di atas, terdapat beberapa asas keadilan yang telah dijaminkan oleh negara kepada masing-masing pihak, baik itu suami ataupun istri. Dua diantara jaminan itu adalah prinsip kesetaraan hak persetujuan yang melibatkan kedua belah pihak, serta tidak ditolerirnya unsur paksaan dalam hubungan keduanya dalam perkawinan. Bentuk persetujuan yang dilahirkan oleh kedua belah pihak meniscayakan adanya titik temu pemahaman atas sebuah permasalahan yang didialogkan. Dialog yang harmonis merupakan wujud dari komunikasi efektif yang seyogyanya diikhtiarkan bersama tanpa melibatkan unsur paksaan di antara masing-masing pihak yang ada. Efektifitas komunikasi tidak hanya sekadar lahir dari satu atau dua kali perbincangan saja, melainkan didukung pula oleh kedewasaan ego masing-masing pihak atas hasil akhir persetujuan yang dapat memberikan kemaslahatan bersama. Salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk melanggengkan rantai kehidupan manusia di muka bumi. Islam memandang bahwa ikatan suami istri yang terbingkai dalam sistem keluarga menjadi pilar utama bagi kehidupan umat manusia. Dalam sebuah penilaian disebutkan bahwa maju-mundurnya sebuah bangsa sangat ditentukan oleh sejauh mana kekokohan pilar yang disebut keluarga (baca: sakinah, mawaddah, rahmah, abadi, tentram nan indah) dapat mewarnai kultur masyarakat yang ada di lingkungannya. Pernikahan sebagai proses perjalanan bersama yang dilakoni oleh pasangan suami-istri bertujuan untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan. Hal ini dipaparkan dengan jelas oleh al Qur-an : Prinsip-prinsip Keadilan Wanita dalam Islam: Sebuah Kajian Pra-nikah _377 Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(QS. al-Rum/30:21). Menanggapi kriteria dalam surah al-Rum itu, Kyai Husein Muhammad Pimpinan Pondok Pesantren Darut Tauhid Arjawinangun Cirebon, menjelaskan bahwa ayat tersebut mengandung tiga hal, yang penting untuk diperhatikan dalam perkawinan: yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah. 6Menurut Kyai Husein, “sakinah”, berasal dari kata sakana. Kata “sakinah” bisa berarti tempat tinggal, menetap dan tenang-tenteram (tidak ada ketakutan). Dengan demikian maka perkawinan merupakan wahana atau tempat di mana orang-orang yang ada di dalamnya, terlindungi dan dapat menjalani kehidupan dengan tenang dan tenteram serta tanpa ada rasa takut. “Mawaddah” dalam penerjemahan Kyai Husein diartikan cinta. Dalam rujukannya atas Muqatil bin Sulaiman, seorang ahli tafsir abad ke 2 H, yang mengatakan bahwa “mawaddah” berarti “mahabbah” (cinta), “nashihah” (nasehat) dan “al shilah” (hubungan yang kuat), yakni hubungan yang di dalamnya tidak terdapat ucapan atau tindakan yang menyakiti. Pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan merupakan ikatan antara dua orang yang diharapkan dapat mewujudkan hubungan saling mencintai, saling menasehati dan saling menghormati. Sementara dalam kata “rahmah” memiliki arti yang sangat mendalam. Dalam pandangan Kyai Husein kata rahmah adalah kasih, kelembutan, kebaikan dan ketulusan. Perkawinan yang dipahami oleh Kyai Husein adalah harapan agung Tuhan agar pasangan suami dan istri kelak dapat menjalin relasi-relasi saling mengasihi, saling memberikan kebaikan dan kelembutan, dan semua itu ditumpahkan dengan hati yang tulus.”7 Ikhtiar mendalami tujuan dari sebuah perkawinan secara bersaman juga memahami relasi ideal kemanusiaan. Jika benar demikian maka harapan masing-masing pihak untuk dapat saling menghargai prinsip 378_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 kesetaraan antara satu dan lainnya, dapat dimulai dengan upaya pemenuhan dan penjagaan atas hak-hak dan martabat mereka secara keseluruhan. Fakta bahwa masih berkembangnya stigma tentang lemah dan rendahnya status salah satu pihak dibandingkan satu pihak lainya, wa bial-khusus dalam konteks perkawinan maka pembangkitan kembali semangat keadilan dan kesetaraan hak terutama bagi pihak yang sudah lama dirugikan tersebut niscaya untuk diimpikan. C.Hak-hak Wanita Pra-nikah 1. Hak Memilih Pasangan Sebagaimana Islam telah meletakkan dasar-dasar dan prinsipprinsip bagi kaum laki-laki dalam memilih pasangan hidup, Islam juga memberikan kebebasan mutlak kepada kaum wanita untuk memilih laki-laki yang diinginkannya saat dilamar. Dengan demikian Islam telah menggabungkan antara hak wali untuk menikahkan wanita dan hak wanita untuk menerima calon suami yang diinginkannya atau menolak calon suami yang tidak diinginkannya. Dalam hal ini Islam selanjutnya melarang para orangtua atau wali untuk bersikap otoriter dalam menikahkan putera-puteri atau suadara-saudara wanita mereka,tanpa adanya persetujuan dari mereka. Ketika seorang wanita telah dewasa dan telah sanggup untuk melakukan pernikahan, maka langkah yang paling baik adalah segera menentukan dan memilih pasangan yang sesuai dengan seleranya. Wanita dapat memilih pasangannya dengan laki-laki yang ia kenal di lingkungan masyarakatnya, baik yang terdekat seperti tetangga maupun di lingkungan pendidikan dan pekerjaan. Secara umum wanita lebih menghendaki laki-laki yang bertanggung jawab, pengertian, sabar, tidak memaksakan kehendak, berasal dari keturunan yang baik, berpendidikan, mempunyai pekerjaan yang mapan, memiliki rumah pribadi hingga mobil pribadi. Walhasil wanita sangat Prinsip-prinsip Keadilan Wanita dalam Islam: Sebuah Kajian Pra-nikah _379 mendambakan seorang pendamping yang nyaris ideal dan tanpa cacat. Dalam kenyataannya keinginan itu tidak selamanya terbukti, sebab sesempurna apapun sosok suami ia tetap adalah manusia biasa dengan segala kelebihan dan kekurangan.8Mengingat manusia memiliki banyak kekurangan, maka Rasulullah SAW. selalu mengingatkan kepada umatnya agar tidak terpedaya dengan ketampanan fisik dan materi belaka, melainkan dianjurkan untuk memilih laki-laki yang tekun beragama dan berakhlak mulia.Sebagaimana Allah SWT, berfirman dalam QS. al-Hujurah ayat 13: Artinya:“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”(QS. Hujurat/49: 13) Latar agama menjadipilihan yang sangat prinsipil bagi wanita sebab pada kriteria inilah, jaminan atasterjaganya kualitas keimanan tidak hanya bernilai ibadah semata. Akan tetapi bersama kualitas pribadi yang shaleh dan berakhlakul karimah itulah kelak akan dapat menciptakan sebuah keluarga yang taat dan penuh dengan kedamaian. Dengan bersandingkan seorang suami yang berakhlak mulia makaakan tampak wujud ketulusan cinta yang hadir dalam cara menggauli sang istri, salah satunya adalah melalui tutur laku dan sapa yang baik, lahir maupun batin.9 Dalam satu kisah al-Qur’an, diceritakan tentang akhlak mulia seorang Musa AS. , ketika membantu dua gadis yang hendak mengambilkan air, di tengah tandusnya padang pasir dengan sikap yang begitu tulus dan tanpa pamrih. Seketika melihat ketulusann yang dicontohkan seorang Musa AS. tersebut, salah seorang dari keduanya menaruh hati kepada Musa, dan mengutarakan niat untuk memilih Musa sebagai pasangan hidup. 380_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 Kisah ini terekam di dalam al-Qur’an pada QS. al-Qashash ayat 26, yang berbunyi: Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya . (QS. al-Qashash/28: 26) Penjabaran dalam kalimat pertama pada ayat di atas adalah al-qawy. Lafadz al-qawy umumnya dimaknai sebagai kekuatan fisik. Konteks yangmelatari pemaknaan kekuatan fisik ini sangat lumrah jika dikaitkan dengantren persainganantar manusia dalam memburu sumber kehidupan, kondisi alam dan jenis pekerjaan yang umumnya diemban oleh masyarakat arab padang pasir. Dalam pemaknaannya yang lain, kata al-Qawy juga memiliki arti bertanggung jawab. Keselarasan antara bentuk tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang suami dengan posisi keluarga dan seorang istri yang diberikan tanggungjawab, tampaknya lebih sesuaidanbernilai sepadan. Karena jika pemaknaan hanya dibatasi oleh kekuatan fisik saja (materi dan ketampanan), maka dalam arus panjang bahtera perkawinan akan mudah larut dan memudar. Dan sebaliknya bahwa jika sifat yang dimiliki itu adalah sebuah tanggung jawab, maka hasil yang akan diciptakan kelak adalah rasa kebercukupan dan keberkahan dari sebuah usaha yang maksimal. Adapun sifat ke dua yang tergambar dari sosok Musa AS. adalah alAmin, artinya orang yang dapat dipercaya. Ketika salah satu dua gadis (anak Nabi Syu’aib) itu berkata kepada ayahnya bahwa Musa adalah seorang yang dapat dipercaya, lalu ayahnya bertanya “apa alasanmu mengatakan demikian?”. Kemudian anaknya bercerita “ketika aku hendak membawanya ke rumah, aku berada di depannya, lalu ia berkata, Prinsip-prinsip Keadilan Wanita dalam Islam: Sebuah Kajian Pra-nikah _381 sebaiknya aku saja yang berjalan di depan dan kalian dibelakangku, kalau nanti sampai di persimpangan jalan, kalian bisa melempar krikil sebagai pertanda ke arah mana kita harus menuju.10 Dalam kisah ini nampaknya wanita sangat mendambakan seorang laki-laki yang dapat dipercaya.Dengan sifat al-amin (dapat dipercaya) maka sosok suami dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam memilih pasangan terutama untuk menentramkan hati pasangan wanita. 2. Hak Wanita dalam Lamaran Sungguh Islam memperbolehkan bagi wanita untuk meminang laki-laki. Islam menetapkan hak wanita selama ia memelihara dasar keshalehan dalam memilih. Tradisi pelamaran wanita atas laki-laki telah dikenal oleh bangsa Arab sebelum Islam. Sebagian dari contoh peristiwa itu adalah yang dilakukan oleh Siti Khadijah binti Khuwailid kepada Rasulullah SAW.11 Dalam Islam proses lamaran temaktub padakamus fiqih dengan sebutan “khitbah”, yangberarti “permintaan”. Dalam penjelasan yang luas, Khitbah dapat diartikan sebagaipernyataan permintaan dari seorang laki-laki kepada pihak seorang wanita untuk mengawininya, baik dilakukan secara langsung atau dengan perantara pihak lain yang dipercayai sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama.12 Menurut Sayid Sabiq, meminang dimaksudkan sebagai permintaan seorang laki-laki kepadawanita, untuk diperkenankan dipilih menjadi seorang istri bagi pihak yang meminta dengan tradisi umum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.13 Sedangkan menurut Abu Zahrah khitbah adalah permohonan seorang laki-laki atas kesediaan seorang wanita tertentu untuk diperistri, yang diajukan kepada wanitaitu sendiri atau kepada kuasanya (wali) dengan penjelasan-penjelasan yang dimaksud.14 Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan sebelum adanya ikatan suami istri, dengan tujuan agar ketika memasuki ke jenjang pernikahan didasari atas sikap kesadaran dan kesukarelaan 382_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 yang didapatkan dari masing-masing pihak. Khitbahatau peminangan bukanlah perkawinan,melainkan janji setia antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk melanjutkan kepada fase pernikahan. Karenanya khitbah tidak berkonsekwensi pada penetapan hak dan penghalalan sesuatu yang haram. Tidak ada yang dihalalkan bagi yang menghitbah maupun yang dikhitbah, kecuali sebatas melihat bakal calon, dengan maksud agar keduanya ridha dan ikhlas dengan kondisi masing-masing pihak. Selebihnya kedua-duanya masih berstatus sebagai orang asing (bukan mahram) sampai akad nikah dilangsungkan.15 Khitbah dipahami sebagaipagar pembuka yang kelak mengantarkan pasangan calon pengantin menuju ke gerbang pernikahan.Karenanya khitbah tidak memiliki konsekuensi apapun seperti yang berlaku pada pernikahan. Khitbah tidak menghalalkan apapun, kecuali hanya untuk saling memandang antara laki-laki dan wanita. Hal ini agar kedua belah pihak dapat saling menerima dengan penuh keikhlasan atas kelebihan dan kekurangan masing-masing. 3. Hak Wanita Menolak Lamaran Pada dasarnya sebuah pernikahan dilandasi oleh rasa saling memiliki kecocokan antara pihak suami dan istri. Namun betapapun idealnya sikap saling cocok di antara pasangan pernikahan mustahil dapat terwujud jika tidak dimulai dari komunikasi awal yang coba dibangun, termasuk dalam tahapan pra nikah, seperti dalam proses lamaran. Proses lamaran yang umumnya diterima oleh pihak wanita sebagai pihak yang akan diperistri oleh sang pelamar, tidak semuanya dapat menerima lamaran begitu saja. Umumnya ada banyak pertimbangan yang melatari wanita untuk memastikan diterima atau ditolaknya lamaranlamaran yang wanita hadapi. Dengan kian ragamnya pertimbangan yang mendasari wanita dalam menentukan lamaran yang diterima, maka selayaknya dapat diimbangi pula dengan sikap legowo dan lapang dada, jika keputusan yang dihasilkan adalah penolakan atas lamaran dari sang wanita. Prinsip-prinsip Keadilan Wanita dalam Islam: Sebuah Kajian Pra-nikah _383 Penolakan lamaran seorang wanita sebaliknya tidak dipandang sebagai bentuk pembangkangan atau sikap ketidaktaatan, melainkan layak dipahami sebagai sikap pertimbangan yang bertanggung jawab dan matang. Menarik untuk ditelusuri sebuah kisah hikmah tentang penolakan lamaran yang pernah dilakukan oleh seorang wanita terhadap laki-laki, yang ternyata dalam penolakan tersebut tidak sedikitpun menyisakan konflik di antara pihak-pihak terkait. Sebagaimana dikisahkan bahwa pada masa Rasulullah SAW. pernah seorang wanita menolak lamaran dari seseorang, dan secara kebetulan yang melamar itu adalah Rasulullah sendiri. Ketika Rasulullah SAW. melamar putri pamannya yang bernama “Ummu Hani” putri Abdul Muthalib setelah meninggal suaminya, maka ia menjawab (wanita tersebut) kepada Rasulullah“Wahai Rasulullah, aku ini wanita yang memelihara dan menanggung nafkah anak-anakku yang yatim, maka anakku masih kecil, ia memiliki empat anak. Padahal hak suami itu berat. Aku takut kalau aku mengurusi suamiku, akan mengabaikan urusan anakku. Kalau aku mengurusi anakku, akan mengabaikan hak suami”. Maka Rasulullah SAW bersabda:“Sesungguhnya diantara yang menunggang unta, yang terbaik adalah wanita Quraisy. Mereka sayang pada anaknya waktu masih kecil dan mengurusi suaminya. Kalau aku tahu bahwa Maryam binti Imran menunggang Unta, pasti aku tidak akan melebihkan orang lain atasnya”.16 Dalam tamsil penolakan atas lamaran Rasulullah SAW, beliau menunjukkan sifat ketauladanan yang baik. Sikap Rasulullah yang sangat menghargai penolakan Ummu Hani tidak sedikitpun diiringi dengan raut merah dan perkataan marah, bahkan sebaliknya Rasulullah malah menyanjungsikap tegas Ummu Hani dan sekaligus memuji-muji kaum wanita Quraisy, yang merupakan latar keluarga dari Ummu Hani. Pada riwayat yang lain, terjadi pada diri Amirul Mukminin, Umar Ibnu Khathab ketika melamar Ummu Kultsum binti Abu Bakar, melalui perantara saudaranya, Siti Aisyah. Ketika Aisyah menanyakan kepada 384_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 Ummu Kalsum, tentang persetujuannya, ternyata ia menolak dan berkata “aku tidak perlu dia”. Aisyah pun menghardiknya seraya berkata: Apakah engkau tidak senang (menerima) Amirul Mukminin? Ia (Ummu Kultsum) pun menjawab, ya. Aku menolaknya karena (Umar Bin Khatab) berkehidupan kasar dan cenderung keras terhadap wanita”.17 Menanggapi penolakan Ummu Kultsum terhadap Umar bin Khattab tersebut, Aisyah tidak ingin memberitahukannya kepada Umar. Aisyah malah meminta kepada Amru bin Ash untuk berkenan sebagai sebagai mediator dalam menyampaikan perihal penolakan Ummu Kulsum kepada Umar. Berkat kecerdikan dan kepiawaian Amr Bin Ash dalam mengantar sesuatu, ia mendatangi Umar dan memulai pembicaraan, Hai Umar, ”ada berita buruk yang sampai kepadaku. Aku berdoa semoga Allah SWT melindungi kau darinya”. Umar bertanya”, Apa itu? Ia balik bertanya, engkau melamar Ummu Kulsum binti Abu Bakar? Umar menjawab, ya. Apakah mau merebut dia dariku? Ia berkata, tidak. Tapi ia masih kecil, ia tumbuh dengan didikan Amirul Mukminin (Abu Bakar) dalam kelembutan, sementara kau punya sifat keras, kami menghormatimu. Kami tidak bisa mengubah salah satu sifat dan akhlakmu. Amru berkata, aku yang akan berkata kepadanya. Aku tunjukkan kau pada yang lebih baik, yakni Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib. Dengan memperistrikannya, nasabmu akan berhubungan pada Rasulullah SAW.18 4. Hak Wanita dalam Menentukan Kafa’ah Dalam istilah fiqih “sejodoh” disebut “kafa’ah”, artinya ialah sama, serupa, seimbang, atau serasi.19Kata ini merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab dan terdapat dalam QS. al-Ikhlas Ayat 4, yang berarti “tidak suatu pun yang sama denganNya”. َو َو ن َو ُك نَّل ُكن ُك ُك ًو ن َو َو ٌدن Kafa’ah atau juga biasa disebut mukafa’ah secara bahasa adalah kesejajaran atau egalitas dalam status dan tingkatan. Secara syariah, Prinsip-prinsip Keadilan Wanita dalam Islam: Sebuah Kajian Pra-nikah _385 kafa’ah adalah kesejajaran antara suami dan istri dalam kriteria-kriteria tertentu yang bisa mencacatkan kehidupan berumah tangga. Namun ada juga ulama yang menyatakan bahwa kafa’ah dikembalikan kepada adat kebiasaan masyarakat.20 Kafa’ah menjadi hal penting bagi setiap individu yang condong hidup dalam keseimbangan dan berposisi proporsional. Dalam surah an-Nur, Allah SWT. Memberikan tamsil yang sangat baik tentang posisi keseimbangan dan asas proporsional. Ayatnya berbunyi: Artinya: Wanita-wanita yang tidak baik adalah untuk laki-laki yang tidak baik, dan laki-laki yang tidak baik adalah buat wanita-wanita yang tidak baik (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan lakilaki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang di tuduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rizki yang mulia (yaitu surga). (QS. Al-Nûr/24:26) Kafa’ah dalam perkawinan merupakan pendorong terciptanya kebahagiaan dalam pergaulan suami dan istri, dan lebih menjamin keselamatan wanita dari kegagalan rumah tangga.Menurut Sayyid Sabiq, “jika laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan, tidaklah diragukan jika kedudukan antara lakilaki dan wanita sebanding akan merupakan faktor kebahagiaan hidup suami istri dan lebih menjamin keselamatan wanita dari kegagalan dan kegoncangan rumah tangga”.21Tujuan perkawinan akan tercapai manakala keseimbangan antara kedua calon mempelai itu terpenuhi. Sebetulnya kafa’ah itu bukanlah salah satu dari syarat mutlak yang harus ada dalam perkawinan, karena pada dasarnya semua manusia di hadapan Allah SWT. itu adalah sama. Bisa saja dalam melangsungkan pernikahan tersebut tidak mempertimbangkan kafa’ah (sebanding) asalkan keduanya, baik calon istri maupun calon suami ikhlas menerima, tetap perkawinan dapat dilaksanakan dan sah nikahnya. Islam memberikan batasan kafa’ah dari segi agama, karena dengan 386_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 agama seseorang akan menjadi lebih baik dan tanggung jawab terhadap keluarganya. Seperti Rasulullah SAW. bersabda dalam sebuah hadits : ُهْيل َ ُه ا َ َُه: َ َا، صلى هلل عليه وسلم َ ا َ يِب َ يِب، وايِب يِبد ليِبه، و يِبِل يِبِل، ا اد يِبن َ َ َ ََ َ َع يِبن الَّنيِب، َََعن َيِب ُه َ ْي َو يِبِلَ َسبيِب َه، َ ايِب َ يِبِل: َ َ ٍع َ يِبَ َ َد َا Artinya:“Dari Abi Hurairah ra berkata Rasulullah SAW: Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia.”(HR. Bukhari)22 Menurut sebagian ulama, yang menjadi ukuran kufu’ adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan dengan ukuran keturunan, pekerjaan, kekayaan dan lain sebagainya.23 Ibnu Hazm berpendapat bahwa kafa’ah itu tidak ada ukurannya, semua manusia adalah sama dihadapan Allah SWT., dan semua manusia adalah bersaudara,24mempunyai hak yang sama, laki-laki muslim menikahi wanita muslimah, seperti dalam kasus Rasulullah mengawinkan Zainab binti Jahs dengan Zaid bin Harisah (bekas budak Rasul), mengawinkan Miqdad (orang miskin) dengan Dhaba’ah binti Zubair bin Abdul Muthallib. Abu Hudzaifah mengawinkan Salim seorang bekas budak wanita Anshar dengan Hindun binti al-Walid bin Utbah bin Robi’ah. Bilal bin Rabah bekas budak menikah dengan saudara wanita Abdu-Rahman bin Auf.25“Rasulullah SAW.telah mengawinkan dua putrinya sendiri dengan Utsman bin Affan, Zainab dengan Abd al-Ash bin Rabi’, sedangkan keduanya adalah dari suku Abd al-Syams, Zainab binti Jahsy dengan Zaid bin Haritsah maula beliau. Abu Huzaifah mengawinkan Salim bekas budak wanita Ansar dengan Hindun binti al-Walid, Bilal bin Rabah kawin dengan saudara wanita Abdurrahman bin Auf. Prinsip-prinsip Keadilan Wanita dalam Islam: Sebuah Kajian Pra-nikah _387 Ibnu Rusyd dalam bukunya Bidayahal-Mujtahid, berkata: pada mazhab Maliki, tidak diperselisihkan lagi bahwa, jika ada seorang gadis dikawinkan oleh ayahnya dengan seorang laki-laki yang peminum khamr atau laki-laki yang fasik, maka ia berhak untuk menolak perkawinannya, dan hakim hendaknya memperhatikan hal ini agar supaya menceraikan antara keduanya. Demikian juga jika ayahnya menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki yang berpenghasilan haram, dan suka mengancam untuk perceraian, maka bagi wanita tersebut mempunyai hak untuk menuntut pembatalan.26 5. Hak menerima Mahar Penerimaan mahar oleh pihak wanita yang diterima dari pihak lakilaki dalam akad nikah adalah salah satu bukti nyata ajaran Islam dalam menghargai sisi kesetaraan manusia. Alih-alih memiliki hak atas mahar, kesengsaraan pihak wanita di zaman pra-Islam justru mengalami ujian hidup yang sangat mengkhawatirkan. Bahkan yang paling mendasar kesempatan kaum wanita untuk hidup sekalipun menjadi kisah yang mustahil ada dan didapatkan pada masa-masa pra Islam. Hingga akhirnya Islam datang dan menghilangkan belenggu kesengsaraan ini. Derajat wanita kemudian diangkat dengan setinggittingginya. Diantara tiga hak yang paling berharga yang diterima oleh wanita dengan datangnya Islam adalah hak untuk hidup, hak untuk menerima waris dan hak menerima mahar. Mahar (maskawin) di dalam Islam diartikan sebagai” hak atas kekayaan (atau sesuatu yang bernilai) bagi wanita, yang diwajibkan kepada laki-laki karena akad nikah”.Mahar adalah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon istri di dalam sighat akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami istri.27 Ada beberapa definisi mahar yang dikemukakan oleh ulama mazhab diantanya mazhab Hanafi yang mendefinisikan mahar sebagai jumlah harta yang menjadi hak istri karena akad perkawinan atau terjadinya senggama dengan sesungguhnya. Ulama lainnya mendefinisikannya 388_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 sebagai harta yang wajib dibayarkan suami kepada istrinya ketika berlangsung akad nikah sebagai imbalan dari kesediaan penyerahan kepada suami (senggama) Ulama mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli. Ulama mazdhab Syafi’i mendefinisikannya sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan disebabkan akad nikah atau senggama. Sedangkan ulama mazhab Hanbali mendefinisikannya sebagai imbalan dari suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim. Termasuk juga kewajiban untuk melakukan senggama. Sedangkan Quraish Shihab mengatakan bahwa mahar adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya.28 Menurut Sayyid Sabiq mahar adalah harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh mempelai laki-laki dengan sebab nikah atau watha.”29 Mahar adalah: “harta benda tertentu yang diberikan oleh seorang lakilaki kepada seorang wanita ketika melakukan akad nikah”. Madzhab syafi’i menyebut bahwa mahar ini sebagai kewajiban suami sebagai syarat mendapatkan manfaat dari istri.30 Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa mahar adalah sesuatu bentuk barang yang bermanfaat yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita karena adanya ikatan perkawinan sebagai pemberian yang wajib. Islam sangat menghargai dan memperhatikan kedudukan wanita, dengan memberikan hak kepadanya, maka mahar hanya diberikan kepada istri bukan kepada orang tuanya sebagai ganti rugi karena anaknya diambil oleh laki-laki lain. Allah SWT berfirman dalam QS.Al-Nisa/4: 4: Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya..” (QS. Al-Nisa/4: 4) Prinsip-prinsip Keadilan Wanita dalam Islam: Sebuah Kajian Pra-nikah _389 Maksud dari ayat di atas adalah bahwa mahar diartikan sebagai pemberian yang wajib, (harus ada) apakah ia diberikan saat ijab qabul atau setelah ijab qabul dalam akad nikah. Jika mahar itu diberikan pada saat akad nikah, ini menunjukkan bahwa seorang laki-laki itu bertanggung jawab kepada istrinya, ditandai dengan pemberian mahar diawal. Dan mahar itu miliknya wanita atau istri, bukan harta bersama dan bukan harta bawaan laki-laki yang diberikan kepada istri. Jika suaminya meminjam maskawin maka suami wajib membayarnya. Lain halnya bila istri itu dengan suka rela memberikan semua atau sebagian mahar kepada suaminya maka ambillah harta itu sebagai harta yang halal. 6. Perjanjian Perkawinan. Dalam literatur fiqh klasik tidak ditemukan bahasan khusus tentang perjanjian perkawinan. Meskipun terdapat bahasan yang berkaitan dengan perjanjian, adalah tema “persyaratan dalam perkawinan”. Kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan. Hukum perjanjian dalam perkawinan adalah mubah,yang berarti dibolehkannya seseorang untuk membuat perjanjian maupun tidak. Jumhur ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk pernjajian itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana hukum memenuhi perjanjian lainnya,bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan, seperti dalam hadits Rasulullah SAW:“Sesungguhnya syarat yang paling utama dipenuhi ialah sesuatu yang dengannya kamu pandang halal hubungan kelamin (perkawinan)”.31 Dalam hadis lain Rasulullah saw, bersabda: ِ ِِ .َح ال َحَر ًاما ُّ َ ْي الْ ُم ْسلم َ ْ َالصلْ ُح َجائٌز ب ُ إِاَّل،ْي َ أ َْو أ،صلْ ًحا َحارَم َح ََلًَّل ِ »والْمسلِمو َن علَى ُشر ِ ِ ا َح ال حراما أ َو أ ، َّل َل ح م ر ح ا ط ر ش َّل إ ، م ه وط ً َ ً ا َ َ ْ َ ََ ْ ْ ُ َ ُ ُْ َ ِ ِالصلْح جائِز ب ْي الْمسل ِ ا .َح ال َحَر ًاما أ َو أ ، َّل َل ح م ر ح ا ح ل ص َّل إ ، ْي م ْ ً َ ا َ َ ْ َ ََ ً ُ ْ ُ َ ْ َ ٌ َ ُ ُّ ِ ِ ِ َح ال حراما َ أ َْو أ، إاَّل َش ْرطًا َحارَم َح ََلًَّل،»والْ ُم ْسل ُمو َن َعلَى ُشُروط ِه ْم َ 390_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 Artinya:”Berdamai dengan sesama muslimin itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal. Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.”(Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Amru bin Auf, diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah. At-Tirmidzi berkata, “Hadits shahih”)32 Nash lainnya yang turut membahas perjanjian perkawinan adalah pendapat dari Umar bin Khattab, Saad bin Abi Waqas, Mu’awiyah, ‘Amru bin ‘Ash, Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Zaid, Thawus, Auza’iy, ishaq dan golongan Hanbali, yang menyebutkan bahwa hukum perjanjian perkawinan dibolehkan. Dengan demikian konsekuensi dari penepatan atas perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak terkait adalah bernilai wajib untuk ditunaikan dan dilaksanakan. Sebagaimana firman Allah swt, dalam surah al-Maidah, ayat pertama berbunyi: ِ َّل يي ءَ َمنُو أ َْوفُو بِااْ ُع ُقود َ يَاأَيُّ َها ا “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji” Dalam satu riwayat dikisahkan, bahwa seseorang pasangan yang menikah telah memiliki perjanjian untuk bertempat tinggal di rumah sang istri. Namun jelang waktu tertentu sang suami berkeinginan untuk mengajak pindah dari rumah sang istri. Melihat keinginan tersebut, pihak keluarga dari sang istri pun mengadukan permasalahan itu kepada Umar bin Khatab. Dalam keputusannya, Umar memastikan bahwa pihak wanita lebih berhak atas janji yang disepakati bersama suami, yaitu untuk menetap kembali bersama di rumah sang istri. Dengan demikian tampaklah ketegasan khalifah Umar saat membatalkan hak dasar seorang suami atas istri, dengan hujjah kesepakatan perjanjian perkawinan. Prinsip-prinsip Keadilan Wanita dalam Islam: Sebuah Kajian Pra-nikah _391 Perjanjian perkawinan dalam pembahasan hukum positif, termaktub secara luas dalam UU Perkawinan, diantaranya pasal 29 (3) Undangundang No 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa Perjanjian Perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Dalam Bab V tentang Perjanjian Perkawinan, tertulis 4 poin penting yang berbunyi: 1.) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, yang mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga tersangkut. 2.) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan keasusilaan. 3.) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. 4.) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Secara rinci bentuk perjanjian perkawinan dibahas juga salah satunya dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu bahwa: Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: a. Ta’lik talak. b. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tapi dalam praktiknya masih jarang yang melakukan,tidak seperti halnya “ta’lik talak”, telah membumi di masyarakat, setiap selesai ijab qabul, langsung naib menganjurkan kepada pihak mempelai laki-laki untuk membaca ta’lik talak. Akan tetapi perjanjian pranikah tidak semua masyarakat mengenal, apalagi melakukannya.Bahkan ada yang beranggapan perjanjian pranikah itu materialistis, egois, tidak rasioalis belum nikah sudah membicarakan harta. Oleh karena itu masih diperlukan sosialisasi kepada masyarakat. 392_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 Dalam bagian ini dirinci beberapa poin atas kemanfaataan dari perjanjian pranikah, diantaranya ialah: a. Perjanjian perkawinan dibuat untuk melindungi secara hukum harta bawaan masing-masing pihak (suami/istri).Artinyaperjanjian perkawinan dapat berfungsi sebagai media hukum untuk menyelesaikan masalah rumah tangga yang terpaksa harus berakhir, baik karena perceraian maupun kematian. Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka akan jelas dibedakan mana yang merupakan harta gono gini (yang perlu dibagi dua secara merata), dan mana yang merupakan harta pribadi masing-masing (tidak perlu dibagi). b. Perjanjian perkawinan juga berguna untuk mengamankan aset dan kondisi ekonomi keluarga. Jika suatu saat terjadi penyitaan terhadap seluruh aset keluarga karena bisnis bangkrut, dengan adanya perjanjian perkawinan, pasangan ekonomi keluarga akan bisa aman. Ketika hendak membuat perjanjian perkawinan pasangan calon pengantin biasanya memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya membentuk suatu rumah tangga saja, namun ada sisi lain yang harus dimasukkan dalam poin-poin perjanjian. Tujuannya tidak lain agar kepentingan mereka tetap terjaga. c. Perjanjian perkawinan juga sangat bermanfaat bagi kepentingan kaum wanita. Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka hak-hak dan keadilan kaum wanita (istri) dapat terlindungi. Perjanjian perkawinan dapat dijadikan pegangan agar suami tidak memonopoli harta gono gini dan harta kekayaan pribadi istrinya. Di samping itu dari sudut pemberdayaan wanita, perjanjian tersebut bisa menjadi alat perlindungan wanita dari segala kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT ).33 Prinsip-prinsip Keadilan Wanita dalam Islam: Sebuah Kajian Pra-nikah _393 Meski telah dituliskan secara gamblang dan jelas, baik dalam UUP dan KHI, namun dalam perakteknya perjanjian perkawinan ini belum familiar bagi masyarakat. Hal ini dipengaruhi budaya ketimuran yang menempatkan pernikahan tidaklah sesuatu yang transaksional. Dalam konteks yang luas, perjanjian perkawinan sangat diperlukan terutama untuk memberikan jaminan atas rasa keadilan bagi setiap pihak dalam berumah tangga.Kepastian akan terjaganya hak-hak perempuan menjadi alasan tersendiri dalam penerapan perjanjian perkawinan ini. Meski tidak menutup fakta bahwa laki-laki juga dapat menjadi korban dalam rumah tangga, namun perjanjian perkawinan lebih identik dengan penjagaan atas hak-hak perempuan. Perjanjian perkawinan dinilai penting dan bermanfaat bagi semua wanita, bukan dalam kapasitas cintanya atas harta, jabatan, atau kekuasaan, melainkan semata mendambakan rasa keadilan. D.Penutup Berdasarkan penjelasan keseluruhan dari tulisan di atas, dapat disimpulkan beberapa prinsip keadilan yang dapat diketahui dan dipahami oleh pihak wanita sebelum memasuki ranah perkawinan. Pertama, tentang hak wanita untuk memilih pasangan. Pada hak pertama ini prinsip keadilan dalam Islam menjamin pihak wanita secara otonom dan tanpa paksaan memilih pasangan yang akan dijadikan pendamping hidup dalam perkawinan. al-Qur’an dengan tegas menyatakan bahwa kejelian wanita dalam menentukan pilihan atas pasangan menjadi utama, tidak hanya karena didasari oleh unsur emosi biologis saja, melainkan diiringi pula oleh pertimbangan kesadaran rasional juga atas dasar prinsip agama. Kedua,hak wanita dalam lamaran atau khitbah, yang dipahami sebagai sikap kemandirian yang diemban dalam menentukan akan terlaksana atau tidaknya sebuah perkawinan. Khitbah kemudian ditamsilkan sebagai pagar pembuka yang kelak mengantarkan pasangan calon 394_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 pengantin menuju ke gerbang pernikahan. Pengertian mendasar khitbah tidak menyebabkan konsekuensi hukum apapun seperti yang berlaku pada pernikahan. Khitbah tidak menghalalkan apapun, kecuali hanya untuk saling memandang antara laki-laki dan wanita, sebagai media untuk saling dapat menerima dengan penuh keihlasan atas kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ketiga, hak wanita menolak lamaran. Seperti halnya hak wanita untuk menerima lamaran dari pihak pelamar, urgensi akan prinsip keadilan yang mengedepankan sisi kesetaraan dan kemandirian pilihan, bahwa hak untuk menolak pun demikian. Dalam penolakan lamaran seorang wanita seghalibnya tidak dipandang sebagai bentuk pembangkangan atau sikap ketidaktaatan, melainkan layak dipahami sebagai sikap pertimbangan yang bertanggung jawab dan matang. Keempat, hak menentukan kafa’ah. Kafa’ah menjadi hal penting bagi setiap individu yang condong hidup dalam keseimbangan dan berposisi proporsional. Islam memberikan batasan kafa’ah dari segi agama, karena dengan agama seseorang akan menjadi lebih baik dan tanggung jawab terhadap keluarganya. Kelima, adalah hak menerima mahar. Penerimaan mahar oleh pihak wanita yang diterima dari pihak laki-laki dalam akad nikah adalah salah satu bukti nyata ajaran Islam dalam menghargai sisi kesetaraan manusia. Nilai kesetaraan yang bersumber dari prinsip keadilan dipandang tidak hanya dari fase historis ketidakadilan wanita pra islam saja, melainkan bahwa penerimaan mahar oleh pihak wanita berpotensi terhadap pola pengaturan keluarga dalam sistem manaejemen ekonomi keluarga. Karena dalam memasuki fase perkawinan posisi suami atau laki-laki sebagai kepala keluarga membutuhkan modal utama yang dititipkan melalui mahar terhadap wanita. Keenam, hak membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dinilai penting dan bermanfaat bagi semua wanita, bukan dalam kapasitas cintanya atas harta, jabatan, atau kekuasaan, melainkan dapat Prinsip-prinsip Keadilan Wanita dalam Islam: Sebuah Kajian Pra-nikah _395 mengantarkan posisi wanita kepada jaminan atas rasa keadilan di dalam perkawinan.Demikian, melalui kajian hak-hak wanita pra-nikah ini, sebaiknya tidak hanya memperkaya tema perkawinan an sich, melainkan dapat juga menjadi pintu masuk untuk memahami prinsip-prinsip keadilan dalam Islam yang lebih luas. 396_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 Daftar Pustaka Husein Muhammad Makalah “Kajian Keluarga Sakinah”, di Masjid Agung Al Azhar Kebayoran Baru, Jakarta, 05 Juni 2005, diselenggarakan atas kerjasama Rahima-Divisi Kajian YISC Al Azhar. Lilik Ummi Kultsum, “Hak-hak perempuan dalam Pernikahan Persfektif Tafsir Sufistik” dalam Jurnal Journal of Qur’an and Hadith Studies, Vol. II Tahun 2013, Jakarta Mukhtar, Kamal, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987 Rusyd, Ibnu, Bidaayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid, Beirut: Dar al-Fikri, t.th Sabiq, Sayyid, Fiqih Sunnah, Alih Bahasa, Moh Thalib, Bandung: Pt. Al – Ma’arif, 1990 Sarifa Suhra “:Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam”, dalam Jurnalal-Ulum, IAIN Gorontalo, Volume. 13 Nomor 2 Shihab, Quraish, Wawasan Al Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas pelbagai persoalan umat, Bandung: Mizan, 2006 al-Subki, Ali Yusuf Fiqh Keluarga Jakarta:Penerbit Amzah, 2010 Pedoman dalam berkeluarga, Susanto, Happy, Pembagian Harta Gono Gini Sat Terjadi Perceraian, Jakarta: PT. Transmedia Pustaka, 2008, Catakan Kedua, Tim Penulis Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Tafsir al-Qur’an tematik, Jakarta: Kamil Pustaka, 2014. Tim Sinergi,Tatanan Berkeluarga Dalam Islam, Jakarta: Lembaga Ketahanan Keluarga Indonesia (LK3I), tanpa tahun, Prinsip-prinsip Keadilan Wanita dalam Islam: Sebuah Kajian Pra-nikah _397 Umar, Nasaruddin, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur’an, Jakarta: Paramadina, 2001 Zahroh, Muhammad Abu, al-Ahwalu Asyahsiah, Mesir: Darul Fikri alArobi, 1957 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Departemen Agama 398_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 Endnotes 1. Sarifa Suhra , “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam”, dalam Gorontalo, 2013, Volume. 13 Nomor 2, h. 374 Jurnalal-Ulum, IAIN 2. Ibid, h. 373 3. Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur’an, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur’an, Jakarta: Paramadina, 2001, h.18-19. 4. Ibid, h. 248 5. UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Departemen Agama 6. Husein Muhammad , Artikel “Kajian Keluarga Sakinah”, di Masjid Agung Al Azhar Kebayoran Baru, Jakarta, 05 Juni 2005, diselenggarakan atas kerjasama Rahima-Divisi Kajian YISC Al Azhar. 7. Husein Muhammad, 2005. 8. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Tafsir al-Qur’an tematik, Jakarta: Kamil Pustaka, 2014. 9. Ibid 10. Ibid 11. Ibnu Hisyam mengatakan, bahwa Khadijah adalah seorang perempuan yang teliti, mulia dan cerdas. Bersamaan dengan kehendak Allah yang memberinya kemuliaan, ketika seorang laki-laki bernama Maysarah menemani Rasulullah dalam berdagang, menceritakan tentang akhlak mulia Rasulullah kepada Khadijah. Dalam waktu yang tak cukup lama Khadjah pun mengutus seseorang kepada Rasulullah, sembari mengatakan, “ Wahai anak pamanku, sesungguhnya aku menyukaimu untuk menjadi kerabatmu”. Selepas itu Rasulullah pun memberitahukan paman-pamannya, sehingga hadirlah Hamzah bin Abdul Muthallib, dan terjadilah peminangan dan pernikahan di antara Khadijah dan Rasulullah. Lihat Dr. Ali Yusuf as-Subki Prinsip-prinsip Keadilan Wanita dalam Islam: Sebuah Kajian Pra-nikah _399 Fiqh Keluarga Pedoman dalam berkeluarga, Jakarta:Penerbit Amzah, 2010, h. 81 dan Ibn Hisyam dalam HamisySirah Nabawiyah Ibn Hisyam Jil.1/h.174. 12. Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987, h. 28. 13. Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Alih Bahasa, Moh Thalib, Bandung: Pt. Al – Ma’arif, 1990, h. 31. 14. Muhammad Abu Zahroh, al-Ahwalu Asyahsiah, Mesir: Darul Fikri al-Arobi, 1957, h. 19 15. Tanpa ada nama pengarang, penerjemah, Tim Sinergi,Tatanan Berkeluarga Dalam Islam, Jakarta: Lembaga Ketahanan Keluarga Indonesia (LK3I), tanpa tahun, h. 105. 16. Lih. Al-Naway, Syarh al-Nawawy ‘ala Muslim, Daar al-Khoir, 1996, hadis nomor 2527 17. Tanpa ada nama pengarang, penerjemah, Tim Sinergi,Tatanan Berkeluarga Dalam Islam, Jakarta: Lembaga Ketahanan Keluarga Indonesia (LK3I), tanpa tahun, h. 105 18. Ibid. 19. Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, ibid, h. 69. 20. Lilik Ummi Kultsum, “Hak-hak perempuan dalam Pernikahan Persfektif Tafsir Sufistik,”dalam Journal of Qur’an and Hadith Studies, Vol. II Tahun 2013, Jakarta, h. 167. 21. Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, ibid, h. 36. 22. Shahih Bukhari, no. 5090. 23. Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, ibid, h. 36. 24. ibid. 25. ibid. 26. Ibnu Rusyd, Bidaayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid, Beirut: Dar alFikri, t.th, h.12. 400_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016 27. Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan,ibid, h. 78. 28. Quraish Shihab, Wawasan Al Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas pelbagai persoalan umat, Bandung: Mizan, 2006, h. 204. 29. Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, ibid, h. 52. 30. Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ‘al Madzhab al-Arba’ah, Beirut: Darul Fikr, t.t, Jil. IV, h. 94 31. Ibid 32. HR Tirmidzi, no. 1271. Hadits hasan shahih. Lihat juga shahih Bukhari 4/451. Sunan ahmad 2/366, Sunan Abu Dawud no. 3594. Hadis ini diriwaytkan dengan beberapa versi kualitas sanad yang berbeda. 33. Happy Susanto, “Pembagian Harta Gono Gini Sat Terjadi Perceraian, Cetakan Kedua, PT. Transmedia Pustaka, Jakarta, 2008, h. 81. Pedoman Transliterasi Revitalisasi Peran dan Fungsi Keluarga _401 _413 Pedoman Transliterasi 402_JurnalBimas BimasIslam IslamVol.5. Vol.9.No.2 No.II2012 2016 414_Jurnal Ketentuan Tulisan _402 A. Ketentuan Tulisan 1. Tulisan merupakan hasil penelitian di bidnag zakat, wakaf, dakwah Islam, pemberdayaan KUA dan hal-hal terkait pengembangan masyarakat Islam lainnya. 2. Karangan ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan perangkat lunak pengolah kata Microsoft Word , font Palatino Linotype, maksimum 25 halaman kuarto minimum 17 halaman dengan spasi satu setengah. 3. Karangan hasil penelitian disusun dengan sistematika sebagai berikut: Judul. Nama Pengarang. Abstract . Keywords . Pendahuluan. Metode Penelitian. Hasil Penelitian. Pembahasan. Kesimpulan dan Saran. Daftar Kepustakaan. Sistematika tersebut dapat disesuaikan untuk penyusunan karangan ilmiah. 4. JUDUL a. Karangan dicetak dengan huruf besar, tebal, dan tidak melebihi 18 kata. b. Nama Pengarang (tanpa gelar), instansi asal, alamat, dan alamat e-mail dicetak di bawah judul. c. Abstract (tidak lebih dari 150 kata) dalam dua bahasa (Indonesia dan Inggris), dan Keywords (3 sampai 5 kata) ditulis dalam bahasa lnggris, satu spasi, dengan huruf miring. d. Tulisan menggunakan endnote e. Daftar Kepustakaan dicantumkan secara urut abjad nama pengarang dengan ketentuan sebagai berikut: • Untuk buku acuan (monograf): Nama belakang pengarang diikuti nama lain. Tahun. Judul Buku. Kota Penerbit: Penerbit. • Untuk karangan dalam buku dengan banyak kontributor: Nama Pengarang. Tahun. “Judul Karangan.” Dalam: Nama Editor. Judul Buku. Kota Prinsip-prinsip Keadilan Wanita Revitalisasi dalam Islam:Peran Sebuah danKajian FungsiPra-nikah Keluarga _403 _415 Penerbit: Penerbit. Halaman. • Untuk karangan dalam jurnal/majalah: Nama Pengarang. Tahun. “Judul Karangan.” Nama Majalah, Volume (Nomor): Halaman. • Untuk karangan dari internet: Nama Pengarang. Tahun. “Judul Karangan.” Alamat di internet ( URL ). Tanggal mengakses karangan tersebut. 5. Gambar diberi nomor dan keterangan di bawahnya, sedangkan Tabel diberi nomor dan keterangan di atasnya. Keduanya sedapat mungkin disatukan dengan file naskah. Bila gambar/tabel dikirimkan secara terpisah, harap dicantumkan dalam lembar tersendiri dengan kualitas yang baik. 6. Naskah karangan dilengkapi dengan biodata singkat pengarang dikirimkan ke alamat kantor Jurnal Bimas Islam berupa naskah tercetak (print out) dengan menyertakan soft copy dalam disket/ flash disk atau dapat dikirim melalui e-mail Jurnal Bimas Islam ([email protected]). 404_Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016