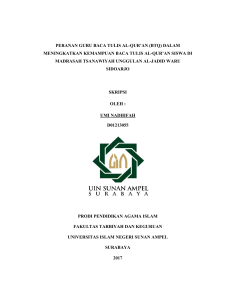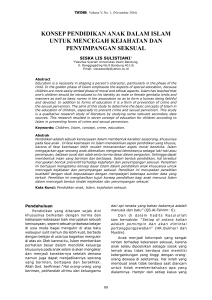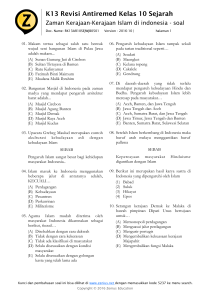filsafat manusia - Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah
advertisement

FILSAFAT MANUSIA (Studi Komparatif antara Abdurrahman Wahid dan Murtadlâ Muthahharî) Skripsi Diajukan dalam Rangka Memenuhi Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Theologi Islam (S.Th. I) Oleh: Hairus Saleh 109033100052 JURUSAN AQIDAH FILSAFAT FAKULTAS USHULUDDIN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1435 H./2014 M. LEMBAR PERNYATAAN Dengan ini saya menyatakan bahwa: 1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ciputat, 08 Juli 2014 Hairus Saleh ii FILSAFAT MANUSIA Antara Abdurrahman Wahid dan Murtadlâ Muthahharî Skripsi Diajukan dalam Rangka Memenuhi Salah Satu Persyaratan untuk Memeroleh Gelar Sarjana Theologi Islam Oleh Hairus Saleh NIM: 109033100052 Di Bawah Bimbingan Dr. Edwin Syarif, MA NIP: 10670918 199703 1 001 JURUSAN AQIDAH FILSAFAT FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1435 H./2014 M. iii PENGESAHAN PANITIA UJIAN Skripsi berjudul FILSAFAT MANUSIA; STUDI KOMPARATIF ANTARA ABDURRAHMAN WAHID DAN MURTADLÂ MUTHAHHARÎ, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 08 Juli 2014. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Theologi Islam (S. Th. I) pada Program Studi Aqidah Filsafat. Jakarta, 08 Juli 2014 Sidang Munaqasyah Ketua Merangkap Anggota Sekretaris Merangkap Anggota Dr. Edwin Syarif, MA Dra. Tien Rohmatin, MA NIP: 10670918 199703 1 001 NIP: 19680803 199403 2 002 Anggota, Dr. Syamsuri, MA NIP: 19590405 198903 1 003 Dr. A. M. Romly, M. Hum NIP: 150 19232 34 iv PEDOMAN TRANSLITERASI ا = a ﻑ = f ب = b ﻕ = q ﺖ = t ك = k ث = ts ﻝ = l ﺝ = j ﻡ = m ﺡ = ḥ ﻦ = n ﺥ = kh ﻭ = w ﺩ = d ﻩ = h ﺫ = dz ء = ’ ﺮ = r ﻯ = y ﺰ = z ﺲ = s Untuk Madd dan Diftong ﺶ = sy آ = â ﺹ = sh ْﺇِﻯ = î ﺽ = dl ﺃُ ْﻭ = û ﻁ = th ﺃَ ْﻭ = aw ﻅ = zh ْﺃَﻯ = ay ﻉ = ‘ ﻍ = gh v ABSTRAK Hairus Saleh Filsafat Manusia (Studi Komparatif antara Pemikiran Abdurrahman Wahid dan Murtadlâ Muthahharî) Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk lain, karena ia mempunyai berbagai potensi yang tidak dimiliki makhluk lain. Potensi itu akan mengarahkan manusia pada tahap mencapai hakikatnya sebagai manusia. Para sufi mengatakan bahwa manusia yang hakiki adalah ia yang mampu memenuhi kebutuhan jiwanya. Pencapaian jiwa manusia akan Tuhannya merupakan tanda bahwa ia sudah mencapai manusia hakiki. Manusia yang demikian tak akan lagi mengedepankan dunia. Tetapi bagi Gus Dur dan Murtadlâ tidak demikian, terdapat sisi di mana manusia harus mengoptimalkan potensi rohaninya untuk memenuhi kebutuhan batin, di sisi lain manusia juga mempunyai potensi jasmani untuk memenuhi kebutuhan lahirnya. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai jiwa tetapi juga hidup di dunia dan berinteraksi dengan orang lain dan alam. Meskipun keduanya sama-sama mengakui potensi lahir dan batin manusia, tetapi mereka mempunyai perbedaan-perbedaan dalam menjabarkan tentang konsep mengenai hakikat manusia. Bahkan puncak pencapaian dari rumusan tersebut juga berbeda. Gus Dur menyimbolkan manusia yang hakiki dengan manusia yang mampu mengoptimalkan seluruh potensinya untuk kesejahteraan. Sedangkan Murtadlâ menyimbolkannya dengan makhluk yang mampu menyeimbangkan segala potensinya demi tercapainya ketauhidan yang benar. Apa yang diuraikan penulis dalam tulisan ini, secara otomatis akan memberikan gambaran-gambaran tentang hubungan pemikiran kaum Sunni dan Syiah. Dari itu pembaca sudah bisa melihat persamaan dan perbedaan pemikiran keduanya. vi KATA PENGANTAR Rasa syukur yang amat sangat mendalam, penulis serahkan jiwa dan raga ini kepada Allah SWT. atas segala rahmat dan kuasa-Nya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarganya, para sahabat serta para pengikutnya yang telah menyebarluaskan warisan kenabian dan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Pada dasarnya, penulisan skripsi ini merupakan suatu respon atas konflik tajam antara pengikut sunni dan syiah di Sampang Madura yang kemudian melahirkan permusuhan yang tak berkesudahan. Isu yang berkembang di masyarakat, konflik antara keduanya disebabkan oleh perbedaan pemahaman terhadap teks-teks agama. Oleh karena itu penulis begitu tertarik untuk mengkomparasikan pemikiran dua tokoh yang masing-masing berasal dari dua aliran tersebut, yaitu Abdurrahman Wahid dan Murtadlâ Muthahharî. Kajian pemikiran kedua tokoh tersebut difokuskan pada pembahasan tentang filsafat manusia. Tentunya, proses penulisan skripsi ini melibatkan banyak kalangan, untuk itu saya merasa perlu menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, terutama peulis sampaikan kepada: 1. Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Komaruddin Hidayat beserta jajarannya. 2. Dr. Edwin Syarif, MA. (Ketua Jurusan Aqidah Filsafat dan juga sebagai pembimbing skripsi), terima kasih telah menyetujui proposal skripsi dan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini vii dengan baik. Dra. Tien Rohmatin, MA (Sekretaris Jurusan Aqidah Filsafat), yang baik hati dan ramah, terima kasih atas nasihat dan bantuannya, akhirnya penulis tetap konsisten menyelesaikan judul skripsi ini. 3. Tak akan lupa dan tak akan pernah terlupakan oleh penulis, menghaturkan beribu-ribu terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Abd. Mun’im Siraj dan Ibunda Hamidah, yang tak hentihentinya memberikan do’a demi lancarnya studi dan penulisan skripsi ini. Juga kepada kakak-kakakku, Siti Maryamah, Siti Hafsoh dan Siti Hasanah yang selalu mendukung serta mengingatkan penulis untuk secepatnya menyelesaikan skripsi. 4. Pimpinan dan segenap civitas akademika Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah banyak membantu kelancaran administrasi dan birokrasi. 5. Para Dosen Fakultas Ushuluddin, yang telah memberikan pencerahan dan ilmu yang luas kepada penulis. 6. Pimpinan dan segenap staf Perpustakaan Utama dan Perpustakaan fakultas Ushuluddin, terima kasih atas pinjaman buku-bukunya yang rela meminjamkan beberapa literatur dalam penulisan skripsi ini. 7. Teman seperjuangan Izaumal Hikmah, Ar Rahmah, Fifin, Burhan, Daqoiq, Fitri M, Ali Humaini, Dwi Astrianingsih dan teman-teman yang lain yang tak bisa disebutkan semua. Terimakasih telah memberikan semangat. Jakarta, 08 Juli 2014 Hairus Saleh viii DAFTAR ISI LEMBAR PERNYATAAN ................................................................................. ii LEMBAR PERSETUJUAN ............................................................................... iii LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................ iv PEDOMAN TRANSLITERASI ......................................................................... v ABSTRAK ........................................................................................................... vi KATA PENGANTAR ........................................................................................ vii DAFTAR ISI ........................................................................................................ ix BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ......................................................................... 1 B. Batasan Masalah ...................................................................................... 6 C. Rumusan Masalah .................................................................................... 6 D. Metode Penelitian ..................................................................................... 6 E. Tinjauan Kepustakaan ............................................................................ 8 F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ........................................................... 9 G. Sistematika Pembahasan ....................................................................... 10 BAB II BIOGRAFI ABDURRAHMAN WAHID DAN MURTADLÂ MUTHAHHARÎ A. Abdurrahman Wahid ............................................................................ 12 1. Riwayat Hidup .................................................................................. 12 2. Karya-karya ...................................................................................... 17 3. Kedudukan Abdurrahman Wahid dalam Pemikiran Islam ........ 20 B. Murtadlâ Muthahharî ........................................................................... 24 1. Riwayat Hidup .................................................................................. 24 2. Karya-karya ...................................................................................... 28 3. Kedudukan Murtadlâ Muthahharî dalam Pemikiran Islam ....... 30 BAB III FILSAFAT MANUSIA DALAM PANDANGAN ABDURRAHMAN WAHID DAN MURTADLÂ MUTHAHHARÎ A. Filsafat Manusia menurut Abdurrahman Wahid ............................... 35 1. Mengenai Hakikat Manusia ............................................................ 35 2. Dimensi-dimensi Manusia ............................................................... 40 B. Filsafat Manusia menurut Murtadlâ Muthahharî .............................. 47 1. Perspektif Murtadlâ Muthahharî tentang Manusia ..................... 47 2. Dimensi-dimensi Manusia ............................................................... 51 ix BAB IV KOMPARASI PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID DAN MURTADLÂ MUTHAHHARÎ TENTANG FILSAFAT MANUSIA A. Pandangan mengenai Ayat-ayat tentang Manusia ............................. 57 B. Pandangan tentang Manusia secara Utuh ........................................... 61 1. Manusia yang Hakiki ........................................................................ 61 2. Dimensi-dimensi Manusia ................................................................. 65 3. Tentang Kebebasan Manusia ........................................................... 69 C. Refleksi Pemikiran Abdurrahman Wahid dan Murtadlâ Muthahharî ................................................................................................................... 76 BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ............................................................................................. 81 B. Saran-saran ............................................................................................. 82 DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 83 x BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Sebagaimana diungkapkan oleh Jan Hendrik Rapar yang diambil dari definisi Plato dalam Pengantar Filsafat bahwa filsafat ialah ilmu yang berupaya untuk memahami hakikat realitas ada dengan mengandalkan akal budi. 1 Karena filsafat mencoba memahi segala realitas yang ada, sehingga objeknya melingkupi segala yang ada termasuk juga manusia. Ketika filsafat berobjekkan manusia, filsafat menjadi ilmu yang mengaji tentang seluk-beluk manusia. Dalam artian, filsafat akan membahas mengenai manusia secara mendalam, baik dari unsur dan fungsi hidupnya. Jika dikaitkan dengan suatu tokoh, itu berarti mengacu pada pemikiran tokoh tersebut mengenai manusia itu sendiri secara mendalam. Maka dari itu, kajian menganai filsafat manusia mengarah pada hakikat manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manusia disebutkan sebagai alam kecil yang merupakan bagian dari alam besar yang ada di atas alam. Ia adalah makhluk yang bernyawa, makhluk antromorphen dan merupakan binatang yang menyusui, akan tetapi juga merupakan makhluk yang dapat mengetahui dan menguasai kekuatan-kekuatan alam di luar dan di dalam dirinya, baik lahir maupun batin.2 1 Jan Hendrik Rapar, Pengantar Filsafat (Yogyakarta: Kanisius, 2010), Cet. Ke-14, h. 15. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), Cet. Ke-1, h. 291. 2 1 2 Al-Qur‟an menyebutkan manusia dengan beberapa istilah, yaitu basyar, insân dan nâs. Istilah basyar mempunyai arti bahwa manusia merupakan makhluk yang terdiri dari karakteristik fisiologis, biologis dan psikologis.3 Istilah insân digunakan dalam al-Qur‟an untuk menunjuk kepada manusia dengan seluruh totalitasnya, yaitu jiwa dan raga. Manusia yang berbeda antara seseorang dengan yang lain akibat perbedaan fisik, mental dan kecerdasan.4 Maka aspek jiwa dan raga inilah yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang memang benar-benar berbeda dengan makhluk lain. Sedangkan istilah nâs digunakan untuk menunjukkan sifat universal manusia atau untuk menunjukkan spesies manusia. Artinya ketika menyebut nâs berarti adanya pengakuan terhadap spisies di dunia ini yaitu manusia.5 Insân merupakan istilah yang sangat cocok untuk menggantikan istilah manusia yang akan dibahas dalam kajian ilmiah ini. Dalam membahas tentang manusia (insân dalam bahasa al-Qur‟an), para tokoh Islam mempunyai beragam pendapat, sesuai dengan latar belakang keilmuannya. Menurut al-Jîlî, manusia merupakan makhluk yang keruhaniannya merupakan unsur pokok dalam hidupnya. Unsur pokok tersebut yang menjadikan manusia memiliki potensi untuk meneladani sifat-sifat Tuhan.6 Dengan usaha ini, sesungguhnya manusia berada dalam proses pengembaraan menuju Tuhan. 3 Charles Kurzman, Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Glogal, terj. Bahrul Ulum dan Heri Junaidi (Jakarta: Paramadina, 2003), h. 300. 4 M. Qurash Shihab, Wawasan al-Qur’an (Bandung: Mizan 1997), h. 278. 5 Bahruddin, Paradigma Psikologi Islam: Studi tentang Elemen Psikologi dari al-Qur’an (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 76. 6 Abdul Karîm Ibnu al-Jîlî, Insân Kâmil: Ikhtisar Memahami Kesejatian Manusia dengan Sang Khâliq hingga Akhir Zaman, terj. Misbah el-Majid (Surabaya: Pustaka Hikma Perdana, 2006), h. 319. 3 Keintiman antara manusia dan Tuhan merupakan titik akhir dari pengembaraan tersebut. Pada tahap ini manusia sesungguhnya sudah mencapai realitasnya sebagai manusia yang hakiki. Berbeda dengan „Alî Syari‘atî, ia memandang bahwa manusia tidak akan pernah mencapai realitasnya, karena antara manusia dan Tuhan selalu terdapat jarak yang memisahkan keduanya. Sehingga manusia pada hakikatnya selalu berada dalam proses menuju realitasnya.7 Jadi meskipun dengan segala unsurunsur individunya ia berpotensi untuk mencapai taraf yang lebih tinggi dari tingkatan kemanusiaan yang dicapainya, tetapi pencapaiannya hanya sebatas terusmenerus maju ke arah realitasnya.8 Kalau kedua tokoh di atas membahas tentang manusia dalam kaitannya dengan penyatuannya dengan Tuhan, tetapi Abudurrahman Wahid dan Murtadlâ Muthahharî membahas tentang manusia yang dikaitkan dengan eksistensi manusia sebagai makhluk yang hidup di dunia dan bertugas untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia, kedua tokoh tersebut menjelaskan dimensi-dimensi manusia yang kemudian diarahkan untuk menjaga keseimbangan berbagai aspek dari hidup manusia. Tetapi keduanya mempunyai perbedaan titik tekan dalam mencapai tujuan dari konsepnya. 7 Gus Dur menjelaskan dimensi-dimensi manusia yang „Alî Syari„atî, Tugas Cendikiawan Muslim, terj. Muhammad Faishol Hasanuddin (Jakarta: YAPI, 1990), h. 68-69. 8 „Alî, Tugas Cendikiawan Muslim, h. 64. 4 dikembangkan itu berujung pada ranah sosial.9 Sedangkan Murtadlâ Muthahharî menjabarkan dimensi-dimensi manusia tersebut berpangkal pada keimanan dan keilmuan.10 Dalam merumuskan konsep tentang hakikat manusia (filsafat manusia), kedua tokoh sama-sama mendapatkan inspirasi dari al-Qur‟an. Al-Qur‟an merupakan landasan utama keduanya dalam konsep tersebut, sehingga dalam membahas tentang manusia, keduanya juga menyertakan ayat-ayat yang kemudian dijabarkan. Maka pembahasan kedua tokoh tentang ayat-ayat mengenai manusia perlu juga dibahasnya. Selain pembahasan mengenai kebebasan manusia dalam menentukan masa depannya. Latar belakang dari penulisan skripsi ini adalah berawal dari konflik Sunni dan Syiah yang terjadi di Sampang pada 26 Agustus 2012. Berdasarkan MUI Jawa Timur konflik tersebut lahir karena perbedaan aliran, yaitu Sunni dan Syiah. Meskipun para peneliti menyebutkan bahwa faktor digerakkannya masyarakat adalah masalah keluarga pemimpin masing-masing kelompok, tetapi faktanya masyarakat itu bergerak atas nama membela Islam dari kesesatan Syiah. Ajaran-ajaran Syiah yang sangat berbeda dengan Sunni yang kemudian dianggap sesat antara lain ialah anggapan Syiah yang memposisikan Imam seperti nabi, anggapan Syiah tentang selainnya adalah pelacur, menghalalkan darah Sunni, 9 Abdurrahman Wahid, Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan (Jakarta: The Wahid Institute, 2007), Cet. Ke-1, h. 30. 10 Murtadlâ Muthahharî, Perspektif al-Qur’an tentang Manusia dan Agama, terj. Haidar Bagir (Bandung: Mizan, 1992), Cet. Ke-6, h. 30. 5 melecehkan Nabi dan Ummul Mu‟minin dan lainnya.11 Ajaran-ajaran ini yang membakar jiwa jihat Sunni Sampang, sehingga mereka menganggap ajaran Syiah sebagai ajaran yang bertentangan dengan Islam. Mereka menjadi tak lagi mampu melihat persamaan-persamaan bahwa mereka juga berlandaskan al-Qur‟an dan hadis. Dari faktor inilah, penulis terpanggil untuk mencari titik persamaan dari kedua aliran tersebut melalui pengkajian terhadap pemikiran masing-masing satu tokoh dari kedua aliran tersebut. Dengan demikian penulis mengambil Abdurrahman Wahid dan Murtadlâ Muthahharî sebagai perwakilan. Alasannya, kedua tokoh tersebut hidup di masa yang sangat dekat, umurnya hanya selisih 20 tahun. Di samping itu, keduanya merupakan tokoh yang mempunyai pengaruh yang cukup besar di Sunni dan Syiah dan bahkan di dunia pemikiran. Kemudian, kedua tokoh tersebut sama-sama tidak hanya membaca buku-buku pemikiran Islam, tetapi juga membaca dan mengkaji secara mendalam buku-buku karya filosof barat. Di tengah perbedaan yang begitu menyeramkan itu, menjadi sangat menarik ketika pemikiran keduanya tersebut dibahas untuk kemudian mencari titik temu yang tepat sekaligus perbedaannya dalam suatu kajian komparasi. Maka untuk mencapai hal itu, penulis mengangkat tema tersebut dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul Filsafat Manusia: Studi Komparasi antara Abdurrahman Wahid dan Murtadlâ Muthahharî. 11 MUI Jawa Timur, Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof. Jawa Timur, No. Kep-01/SKF-MUI/JTM/I2012, Tentang kesesatan ajaran Syiah. 6 B. Batasan Masalah Penulis memfokuskan pembatasan masalah skripsi ini pada pemikiran tentang manusia menurut Abdurrahman Wahid dan Murtadlâ Muthahharî yang ditinjau dari aspek penafsiran tentang manusia, hakikat, unsur-unsur dan kebebasan manusia. Dalam judul skripsi menyebutkan istilah filsafat manusia. Maksud dari istilah filsafat manusia itu sendiri ialah kajian yang mendalam mengenai hakikat manusia itu sendiri. Pengertian mengenai filsafat sebagai kajian yang mendalam diambil dari buku Kamus Filsafat yang ditulis oleh Loren Bagus. Tepatnya, ia menjelaskan bahwa “filsafat merupakan penyelidikan kritis atas pernyataanpernyataan yang diajukan oleh berbagai bidang pengetahuan”.12 C. Rumusan Masalah Berdasarkan batasan masalah di atas, masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: bagaimana konsep manusia menurut Abdurrahman Wahid dan Murtadlâ Muthahharî? Apa persamaan dan perbedaan pemikiran keduanya tentang filsafat manusia? D. Metode Penelitian Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode studi pustaka dengan rujukan buku primer tulisan-tulisan karya Abudurrahman Wahid, seperti Islam Kosmopolitan, Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan, 12 Loren Bagus, Kamus Filsafat (Jakarta: Gramedia, 2005), Cet. Ke-4, h. 242. 7 Islamku, Islam Anda dan Islam Kita, Prisma Pemikiran Gus Dur dan lain-lain. Sedangkan mengenai tulisan pemikiran Murtadlâ Muthahharî, buku yang akan dijadikan kajian utama ialah Insân Kâmil, yang diterjemahkan oleh Abdillâh Ḥâmid Baʻabud menjadi Manusia Seutuhnya, Man and Universe, Bedah Tuntas Fitrah, Perspektif al-Qur’an tentang Manusia dan Agama karya Murtadlâ yang disunting Haidar Bagir dan lain-lain. Sedangkan sumber sekunder ialah karya-karya yang membahas atau yang berkaitan dengan manusia. Sumber sekunder ini akan digunakan untuk menganalisis pemikiran Abdurrahman Wahid dan Murtadlâ Muthahharî mengenai manusia sekaligus persamaan dan perbedaannya yang kemudian akan ditemukan titik temu antara kedua pemikiran tersebut. Dalam pembahasan, penulis menggunakan metode deskriptif-analitik, yaitu menggunakan sumber-sumber yang ada, lalu mendeskripsikannya, kemudian dianalisis mengenai bagaimana pemkiran Abdurrahman Wahid dan Murtadlâ Muthahharî tentang menusia sekaligus titik temunya. Sedangkan secara teknis, penulisan skripsi ini didasarkan pada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Thesis, dan Disertasi), Jakarta, Ceqda, 2007. Sedangkan Paramadina. transeliterasi didasarkan pada pedoman transeliterasi 8 E. Tinjauan Kepustakaan Berdasarkan hasil pengamatan penulis di perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, sudah terdapat beberapa penelitian yang mengaji pemikiran Abdurrahman Wahid dan Murtadlâ Muthahharî, tetapi tidak satu pun dari pembahasan tersebut mengkomparasikan antara pemikiran kedua tokoh tersebut mengenai kajian tentang manusia. Di antara penelitian-penelitian tersebut yaitu: Penelitian skripsi yang berhubungan dengan Murtadlâ Muthahharî ialah Pertama, skripsi yang berjudul Kebebasan Manusia dalam Persepektif John Stuart Mill dan Murtadlâ Muthahharî (Sebuah Studi Komparasi) yang ditulis oleh Yuli Astuti pada tahun 2001. Yuli memfokuskan pada kebebasan manusia yang menurutnya terdapat perbedaan dan persamaan dalam pemikiran kedua tokoh tersebut. Kedua, Kejahatan dan Keadilan Tuhan dalam Perspektif Teologi Murtadlâ Muthahharî yang merupakan skripsi Izkar Sobah pada tahun 2006. Skripsi ini difokuskan pada keadilan Tuhan dan kejahatan yang tidak membuatnya untuk tidak adil. Ketiga Konsep Fitrah Murtadlâ Muthahharî yang ditulis oleh Muniroh pada tahun 2008. Dalam skripsi ini ia membahas fitrah yang berkaitan dengan masalah-masalah kemanusiaan dan prinsip-prinsip berpikir yang tak lain bersifat fitrah. Keempat, Konsep Zuhud Murtadlâ Muthahharî yang ditulis Nurdin Kadir pada tahun 2008. Ia memokuskan penulisannya pada zuhud yang akan mengakibatkan seseorang merasa puas dengan kehidupan yang sederhana. Keenam ialah Pemikiran Murtadlâ Muthahharî tentang Filsafat Sejarah yang ditulis oleh Muslim pada tahun 2011. Skripsi ini difokuskan pada filsafat sejarah 9 Murtadlâ yang kemudian dilanjutkan pada kritiknya terhadap materialisme dialektis dan materialisme historis Karl Marx. Sedangkan karya ilmiah yang berkaitan dengan Gus Dur di antaranya ialah Kontroversi Kebijakan Politik Presiden Abdurrahman Wahid pada Era Reformasi yang ditulis oleh asep hikmatillah tahun 2006. Penelitian ini membahas tentang kebijakan presiden mengenai pencabutan TAP MPR tentang pelarangan ajaran Komunisme, Marxisme, Leninisme; penghapusan Departemen Sosial, juga penerahangan, badan pemantapan stabilitas nasional dan lembaga penelitian khusus. Pandangan Abdurrahman Wahid terhadap Pancasila sebagai Asas Negara yang ditulis oleh Warno pada tahun 2009. Skipsi ini mengaji tentang hubungan antara agama dan negara. Hal ini dilakukan untuk menemukan makna Pancasila dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari banyak suku, ras, agama serta budaya. Dan Demokrasi dalam Pandangan Abdurrahman Wahid yang ditulis oleh Ato Sugiarto pada tahun 2010. Skipsi ini membahas tentang pilar-pilar demokrasi, relasi Islam dengan demokrasi dan analisis pemikiran Abdurrahman Wahid tentang demokrasi. F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara pemikiran Abdurrahman Wahid yang merupakan tokoh besar Sunni dan Murtadlâ Muthahharî sebagai tokoh berpengaruh Syiah tentang filsafat manusia. 10 Sedangkan kegunaan dari penelitian ini meliputi kegunaan praktis dan akademis. Kegunaan praktis dari penelitian ini yaitu: Pertama, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap pertikaian antara aliran Sunni dan Syiah khususnya di Sampang, bahwa ajaran kedua aliran tersebut tidak bertentangan dan bahkan di beberapa aspek mempunyai persamaan-persamaan yang dengan hal itu kedua aliran tersebut dapat hidup berdampingan dengan damai. Kedua, penelitian ini diharapkan mampu memberikan model terbaik kepada seluruh umat tentang hakikat manusia. Sedangkan kegunaan akademisnya ialah penelitian ini berguna untuk memperkaya khazanah intelektual Islam dan Indonesia. G. Sistematika Penulisan Untuk lebih mempermudah pembahasan dan penulisan pada skripsi ini, maka penulis mengklasifikasikan permasalahan dalam beberapa bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut: Bab I merupakan Bab Pendahuluan, memuat latar belakang, rumusan dan batasan masalah, metode penelitian, tinjauan kepustakaan, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan. Bab II akan dijelaskan mengenai biografi Abdurrahman Wahid dan Murtadlâ Muthahharî. Dalam bab ini penulis akan membahas biografinya yang perlu diangkat dalam penelitian ini. Di dalam biografi tersebut, terdapat sub pembahasan yang terdiri dari riwayat hidup dan kedudukan kedua tokoh tersebut dalam pemikiran Islam. 11 Mengenai pemikiran filsafat manusianya, penulis akan membahas selukbeluk pemikirannya mengenai filsafat manusia seperti aspek-aspek kemanusian manusia yang memang harus ditekankan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga aspek kemanusiaan itu perlu dilindungi. Tetapi tidak hanya itu, hal-hal yang berkaitan dengan konsep manusia akan penulis ungkapkan dalam bab ini. Bab III akan dijelaskan tentang pemikiran kedua tokoh yang penulis bahas mengenai filsafat manusia. Filsafat manusia tersebut terdiri dari kajian tentang manusia secara hakiki beserta dimensi-dimensi kemanusiaan manusia yang memang tertanam dalam diri manusia. Bab IV menjelaskan tentang komparasi pemikiran Abdurrahman Wahid dengan Murtadlâ Muthahharî mengenai pemikiran filsafat manusia. Di kesempatan ini penulis akan membahas persamaan sekaligus perbedaan pemikiran keduanya mengenai filsafat manusia beserta analisis terhadap pemikiran kedua tokoh tentang filsafat manusia. Sedangkan Bab V adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. BAB II BIOGRAFI ABDURRAHMAN WAHID DAN MURTADLÂ MUTHAHHARÎ A. Abdurrahman Wahid 1. Riwayat Hidup Nama Abdurrahaman Wahid sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Abdurrahman Wahid dikenal juga dengan nama Gus Dur. Gus adalah panggilan kehormatan untuk putra dari keluarga Kiai. Gus itu sendiri adalah kependekan dari kata bagus. Di Madura, gus (bagus) dikenal dengan istilah lora. Dia adalah anak pertama dari enam bersaudara dari pasangan priyai terkemuka di Indonesia. Bapaknya, Kiai Abdul Wahid Hasyim adalah putra Kiai Hasyim Asy‟ari yang merupakan pendiri oraganisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, jamʻiyah Nahdlatul Ulama (NU). Sedangkan ibunya, Nyai Sholehah, adalah putri dari tokoh besar NU dan juga seorang Kiai terkemuka, Kiai Bisri Syamsuri.12 Mengenai hari kelahiran Gus Dur, beberapa penulis berbeda pendapat. Tim Institute of Culture and Religion Studies (INCRES), id.wikipedia.org dan beberapa penulis menyebutkan bahwa tanggal kelahirannya bertepatan pada 4 Agustus 1940 M. Sedangkan Greg Barton menyebutkan bahwa pada 7 September adalah tanggal kelahiran Gus Dur. Alasannya, penanggalan 12 Tim Institute of Culture and Religion Studies (INCRES), Beyond the Symbols: Jejak Antropologis Pemikiran dan Gerakan Gus Dur (Bandung: INCRES, 2000), Cet. Ke-1, h. 4. 12 13 kelahiran Gus Dur berdasarkan pada penanggalan Islam, yaitu 4 Sya‟ban yang bertepatan pada tanggal 7 September 1940 M.13 Tetapi Greg Barton dan Tim Institut of Culture and Religion Studies (INCRES) sepakat bahwa Gus Dur adalah keturunan dari Lembu Peteng (raja Brawijaya VI) melalui Jaka Tingkir (putera Lembu Peteng), pangeran Bawana (putera Jaka Tingkir).14 Jaka tingkir adalah tokoh yang pertamakali dianggap sebagai orang yang memperkenalkan Islam di daerah pantai timur laut pulau Jawa. Sedangkan pangeran Bawana merupakan orang yang rela meninggalkan kemegahan kerajaan demi mengajar sufisme kepada masyarakat.15 Sejak belajar bersama kakeknya, Gus Dur memang sudah terbiasa hidup sederhana. Dalam pendidikan ia justru belajar di sekolah-sekolah sederhana. Di masa kecil ia belajar di pondok pesantren yang diasuh kakeknya. Ketika di Jakarta, ia belajar di sekolah dasar KRIS (Jakarta Pusat) dan pindah ke SD Matraman Pertiwi.16 Untuk tingkat sekolah menengah pertama ia sekolah di Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP) Tanah Abang, dan pindah ke SMEP Yogyakarta. Di samping itu ia juga belajar ilmu agama kepada Kiai pengasuh pondok pesantren seperti KH. Maksum Ali, KH. Fatah, KH. Masduki dan KH. Bisri Syamsuri.17 Selain kakeknya, ayah Gus Dur, Wahid Hasyim (pemimpin Islam sekaligus pejabat kementerian agama) mempunyai jasa yang besar terhadap 13 Greg Barton, Biografi Gus Dur, terj. Lia Hua (Yogyakarta: LKiS, 2003), Cet. Ke-1, h. 25. Tim INCRES, Beyond the Symbols, h. 6. 15 Greg, Biografi Gus Dur, h. 27. 16 Greg, Biografi Gus Dur, h. 70. 17 Ahmad Bahar, Biografi Kiai Politik Abdurrahman Wahid: Gagasan dan Pemikiran (Jakarta: Bina Utama, 1999), h. 4-5. 14 14 perkembangan intelektual Gus Dur. Ayahnyalah yang mengajarkannya banyak hal, terutama dalam hal pluralitas dan toleransi. Karena Gus Dur adalah orang yang selalu menemani Wahid Hasyim dalam setiap aktivitasnya dengan berbagai golongan, termasuk dengan Tan Malaka.18 Gus Dur memang sosok yang mempunyai kebiasan berbeda dengan lainnya. Sejak kecil ia sudah terbiasa berbaur dengan berbagai golongan dan keadaan sebagaimana diajarkan kakek dan ayahnya. Kebiasaan ini turut memperkaya khazanah intelektualnya, karena setiap orang yang pernah berinteraksi dengannya pasti membawa budaya, ideologi serta kemampuan intelektualnya. Seperti Willem Buhl, di samping mengajarinya bahasa Belanda, ia juga menyuguhkan musik klasik ala Eropa.19 Inilah modal awal Gus Dur yang akan menyadarkanya tentang pentingnya saling menghormati dan pentingnya memanusiakan manusia. Dari aspek intelektual, Gus Dur juga merupakan sosok yang mempunyai kebiasaan berbeda dengan orang lain seusianya. Ketika di Jakarta, ia sering membaca buku di Perpustakaan Umum dan akrab dengan berbagai majalan, surat kabar, novel, filsafat, dokumen sejarah manca negara, cerita silat hingga fiksi sastra.20 Hal itu didukung oleh anjuran ayahnya untuk membaca buku apa saja yang disukai dan kemudian secara terbuka membicarakan ide-ide yang mereka temukan.21 18 Greg, Biografi Gus Dur, h. 35. Tim INCRES, Beyond the Symbols, h. 6. 20 Tim INCRES, Beyond the Symbols, h. 7. 21 Greg, Biografi Gus Dur, h. 40. 19 15 Maka dari itu, menjadi sangat wajar jika dalam usia 15 tahun saja ia sudah membaca buku-buku berat seperti Das Kapital karya Karl Marx, bukubuku filsafat Plato, Thales, novel-novel William Bocher dan Romantisme Revolusioner karangan Lenin Vladimir Ilych.22 Bacaannya tentang pemikiran filsafat barat juga diteruskan sampai ia kuliah di Universitas Baghdad Iraq. Ia banyak membaca pemikiran Emile Durkheim dan filosof-filosof Barat lainnya.23 Tetapi yang tidak kalah bahwa ia juga belajar dengan tekun tentang buku-buku Islam tradisional sejak keberadaannya di pondok pesantren, Universitas al-Azhar Mesir dan Universitas Baghdad. Serta banyak membaca tentang sastra dan kebudayaan Arab, dan teori sosial.24 Meskipun Gus Dur banyak membaca buku tentang pemikiran-pemikiran barat, tetapi tidak kemudian melupakan bacaan-bacaan dan ajaran Islam tradisional yang merupakan identitas ideologinya. Pemikiran-pemikiran barat tampak banyak memengaruhinya, sehingga ia mampu berpikir secara sistematis. Yaitu kajian-kajian yang dikelutinya dilakukan secara empiris dengan menggunakan pisau mitodologi yang tajam. Ia juga tetap mempertahankan ajaran spritualitas dengan mengunjungi makam para wali. Di samping itu ia mendapat pengokohan ajaran spiritualitasnya dengan menggeluti ajaran Imam Junaidi al-Baghdadi.25 22 INCRES, Beyond the Symbols, h. 9. Greg Barton, “Liberalisme: Dasar-dasar Progresivitas Pemikiran Abdurrahman Wahid” dalam Greg Barton dan Greg Fealy (ed), Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul UlamaNegara, terj. Ahmad Suaedy dkk (Yogyakarta: LKiS, 1997), h. 170. 24 Ibid, h. 168. 25 Budi Hadrianto, 50 Tokoh Islam Liberal Indonesia Pengusung Ide Sekulerisme, Pluralisme, dan Liberalisme Agama (Jakarta: Hujjah Press, 2007), h. 18. 23 16 Dalam pandangannya mengenai Islam, ia banyak mengaji mengenai Islam tradisional dan menghormati kebudayaan lokal. Hal itu yang menjadikan Gus Dur tidak terbatasi oleh ideologi, sehingga ia mempunyai ruang yang lebih luas di ranah nasional dibandingkan dengan Kiai lain. Dengan demikian ia dijuluki dengan sebutan Kiai ketoprak.26 Tidak puas-puasnya Gus Dur belajar. Meskipun sudah menjabat sebagai presiden, ia tetap tidak gengsi untuk terus belajar pada orang-orang yang dianggap lebih hebat darinya. Orang yang dijadikannya guru selain guru di pesantren ialah Presiden Kim Dae Jung yang merupakan Presiden Seoul dan Sulakhshi Bharaksa dari Thailand. Keduanya ialah guru Gus Dur yang masih hidup di masanya. Sedangkan gurunya yang sudah meninggal di antaranya Ialah Sun Yat Sen, Jose Rizal, Jawaharal Nehru, Mahatma Gandhi dan Soekarno.27 Sepulangnya ke Indonesia, Gus Dur banyak berkiprah di dunia penulisan dan aktivitas akademis lainnya. Misalnya ia aktif menulis di Majalah Tempo, Jurnah Prisma, Kompas dan Pelita.28 Kemudian dia mendirikan Forum Demokrasi (FORDEM). Sekaligus penggagas berdirinya Gerakan Anti Diskriminasi (Gandi). Gus Dur juga pernah menjadi salah seorang presiden pada Konfrensi Dunia untuk Agama dan Perdamaian yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Ia juga pernah menjadi anggota Pembina Simon Pereze untuk Perdamaian yang 26 Listiyono Santoso, Teologi Politik Gus Dur (Yogyakarta: al-Ruzz, 2004), h. 71. Tim INReS, Beyond the Symbols, h. 22. 28 Ibid, h. 19. 27 17 Bermarkas di Tel Aviv, Israel dan menjadi dewan penasehat pada Internasional Dialoque Foundation on Perspective Studies of Syariah and Secular Law, di Den Haag, Belanda.29 Berbagai penghargaan juga pernah dinobatkan kepadanya. Salah satunya ialah penghargaan Nobel Asia yang disebut Hadiah Ramon Magsaysay yang digelar di Manila, Filipina. Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan keterlibatan yang besar dan mempunyai komitmen yang tinggi terhadap demokrasi serta upaya menumbuhkan toleransi antar umat beragama di Indonesia.30 Penghargaan yang diterima tersebut tidak salah, karena selama hidupnya Gus Dur memang memerjuangkan kemanusiaan lewat demokrasi. Menurut putrinya, Yenny Zannuba Wahid, di sambutan dalam suatu buku, bahwa Gus Dur adalah orang yang sepanjang hidupnya berjuang untuk kemanusiaan.31 2. Karya-Karya Gus Dur memang terkenal sebagai akademisi yang produktif dalam tulis menulis. Karya-karyanya banyak menyebar di berbagai media. Tulisan-tulisan itu kemudian diformat dalam bentuk buku. Di antara bukunya ialah: Tuhan tidak Perlu Dibela merupakan buku kumpulan tulisannya yang dimuat di Tempo dari tahun 1970-an sampai 1990-an. Dalam buku ini, Gus Dur 29 Ahmad, Biografi Kiai Politik Abdurrahman Wahid, h. 37. Mujamil Qamar, NU Liberal dari Tradisionalisme ke Universalisme Islam (Bandung: Mizan, 2002), h. 167. 31 Yenny Zannuba Wahid, “Gus Dur: Seorang Pejuang Kemanusiaan,” Rumadi (ed), Damai Bersama Gus Dur (Jakarta: Kompas, 2010), h. xix. 30 18 menjelaskan tentang paradoks-paradoks yang terjadi di sekitar pemikiran Islam, perdebatan politik, sosial keagamaan dan ideologi antarkelompok dalam konteks kebangsaan dan ke-Indonesia-an. Prisma Pemikiran Gus Dur merupakan kumpulan tulisan Gus Dur yang dimuat di jurnal Prisma yang dicetak dalam bentuk buku. Spektrum yang menjadi perhatiannya dalam tulisan ini meliputi politik, ideologi, nasionalisme, gerakan keagamaan, pemikiran sosial dan budaya. Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan merupakan pemikiran Gus Dur dalam merespon isu-isu yang dianggap aktual sejak 1980-an hingga 1990-an. Selain itu, buku ini berisi kumpulan tulisan-tulisan Gus Dur yang telah berserakan di media lokal maupun nasional. Dalam buku itu, ia menjelaskan tentang Islam yang multi wajah, wajah manusiawi. Islam, dalam buku tersebut, adalah agama yang tampil sejuk, pluralis, serta demokratis. Agama Islam menjadi agama yang melindungi umat manusia, bukan agama yang menebar ketakutan kepada umat agama lain. Pergulatan Negara, Islam dan Kebudayaan, karya Gus Dur ini menjelaskan tentang sebuah negara yang tidak seharusnya berurusan dengan kebudayaan. Karena kebudayaan merupakan seni hidup (the art of living) atau kehidupan sosial manusiawi (human social life) yang terbangun dari interaksi antar manusia; individu maupun kelompok. Kebudayaan dengan demikian adalah representasi emansipasi manusia ke arah yang lebih survive. Intervensi negara atas (meminjam istilah Gus Dur) birokratisasi-kebudayaan hanya akan 19 memutarnya ke arah kebalikan, yakni pembekuan daya cipta masyarakat yang sedang berada dalam perubahan besar-besaran. Karya Gus Dur yang berjudul Kiai Nyentrik: Membela Pemerintah ini dikumpulkan dari kolom-kolom yang dia tulis di majalah Tempo era 1970-an dan 1980-an. Esai-esai ini bertutur tentang rasionalitas yang penuh warna, yang bergerak antara ortodoksi dan penyiasatan pragmatik, agar kehidupan tetap berlangsung. Menggerakkan Tradisi; Esai-Esai Pesantren, buku ini merupakan kumpulan essai Gus Dur tentang pesantren, yang mengambil format hubungan pesantren, negara, pembangunan, dan juga deskripsi atas kebudayaan pesantren. Deskripsi Gus Dur ini turut mempersempit kesenjangan dan kekeliruan pengertian antara pihak luar dan pihak dalam pesantren. Tawaran pembaruan yang dikemukakan Gus Dur untuk pesantren, seperti hal penyusunan kurikulum, peningkatan sarana, pembenahan manajemen kepemimpinan, pengembangan watak mandiri, dan beberapa yang lainnya tetap merupakan agenda pesantren hingga sekarang. Buku selanjutnya ialah Islamku, Islam Anda, Islam Kita. Dalam buku ini Gus Dur menjelaskan tentang apa yang ia lihat mengenai kejayaan Islam yang terletak pada kemampuan agama Islam untuk berkembang secara kultural. Dalam hal ini, ia menulak konsep mengenai negara Islam. Karena menurutnya Islam merupakan jalan hidup yang tak memiliki konsep jelas tentang negara. 20 3. Kedudukan Abdurrahman Wahid dalam Pemikiran Islam Dalam ranah pemikiran Islam Indonesia, Gus Dur mempunyai posisi yang cukup tinggi dan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap pemikiran Islam pada masa itu dan sesudahnya. Hal ini tidak mengherankan, karena kapasitas keilmuan Gus Dur yang tidak diragukan lagi kehebatannya, baik mengenai keilmuan agama maupun keilmuan lain. Tidak hanya itu, yang menjadikannya mempunyai pengaruh dan wibawa yang hebat terhadap umat Islam Indonesia ialah posisinya sebagai cucu dari pemimpin besar kelompok Islam terbesar sedunia, yaitu Hasyim Asyʻarî. Berdasarkan perjalanan intelektualnya, Gus Dur dibentuk oleh pendidikan Islam klasik dan pendidikan Barat modern. Kedua pendidikan tersebut memberikan modal yang sangat baik untuk mengembangkan pemikirannya mengenai Islam Indonesia. Tampaknya kedua pendidikan tersebut yang menjadikannya mempunyai cara pandang yang lebih luas dibandingkan dengan tokoh Islam lainnya, yaitu pandangan yang menekankan pada hal yang bersifat substansial.32 Hal yang tidak dapat dilupakan ialah Gus Dur merupakan bagian dari gerakan baru dalam pemikiran Islam di Indonesia.33 Gerakan baru yang menekankan pemahaman Islam yang terbuka, terutama dalam menerima kenyataan tentang kemajemukan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. 32 33 Tim INCReS, Beyond the Symbols, h. 55. Greg, Biografi Gus Dur, h. 134. 21 Hal tersebut kemudian menekankan sikap toleran dan harmonis dalam hubungannya dengan komunitas lain.34 Gus Dur dikenal dengan seorang pemikir Islam yang sangat bijak. Dalam memahami ajaran Islam, ia juga mempertimbangkan kearifan lokal yang menurutnya harus tetap dipertahankan35 tanpa harus menghilangkan ajaran keimanan dan peribadatan formal.36 Karena budaya lokal merupakan identitas suatu masyarakat yang bersangkutan, yang kemudian membedakannya dengan masyarakat lain. Di samping itu, Gus Dur merupakan pemikir Islam yang disamakan dengan filosof Yunani ternama yang molontarkan komentar-komentar humoris. Filosof tersebut ialah Socrates.37 Sebagai tokoh intelektual yang disamakan dengan Socrates, keagungan Gus Dur dalam ranah akademis sudah sewajarnya menjadi panutan umat. Bapak Humanis Islam adalah sebutan yang tidak berlebihan untuk Gus Dur. Ia hadir di dunia memang untuk memperjuangkan hak-hak kemanusiaan. Tak pernah ada rasa ragu dan takut dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia. Dalam memperjuangkan kemanusiaan, Gus Dur selalu menghindari kekerasan sebagaimana dilakukan salah satu tokoh favoritnya, Mahatma 34 Abdurrahman Wahid, “Pemikiran Islam yang Brilian,” dalam Badiatul Rozikin, dkk, 101 Jejak Tokoh Islam Indonesia (Yogyakarta: E-Nusantara, 2009), h. 38. 35 M. Hanif Dhakiri, 41 Warisan Kebesaran Gus Dur (Yogjakarta: LKiS, 2010), h. 126. 36 Abdurrahman Wahid, Tuhan tidak Perlu Dibela, h. 92. 37 M. Hanif Dhakiri, 41 Warisan Kebesarans Gus Dur, h. 22. 22 Gandhi.38 Bahkan, dia pernah berpesan seandainya ia wafat, di batu nisan hendaknya dituliskan dengan kalimat “di sini dikubur seorang humanis.”39 Dalam suasana intelektual umat Islam yang mulai stagnan, di tengah keterbungkaman intelektual muslim Indonesia karena tekanan sesepuhnya yang terus menghantui kaum muda untuk berpikir kritis, Gus Dur tampil sebagai pahlawan yang cukup gagah dan sukses dalam mendorong dan memupuk tumbuhnya intelektual umat Islam Indonesia. Dialah, Gus Dur yang melahirkan dan menumbuh suburkan kultur kaum muda NU. Kaum muda yang melahirkan pemikiran-pemikiran yang mencengangkan dalam merespon isu-isu modern.40 Djohan Efendi juga memberikan penilaian yang sama mengenai hal ini, bahwa era kepemimpinan Gus Dur di organisasi Islam terbesar dunia itu telah melahirkan banyak intelektual muda yang punya kompetensi yang hebat dan kreatif dalam merespon problematika zaman yang datang silih berganti. Hal itulah kiranya yang menjadikan NU tidak tergoncang dikala arus globalisasi membanjiri dunia Islam Indonesia. Tema-tema yang menjadi ajang dialog aktif dan terbuka antarintelektual di antaranya mengenai isu tentang Islam dan negara, Islam dan budaya lokal, Islam dan modernisme, Islam dan kemanusiaan. Gus Dur sangat aktif merespon isu-isu tersebut dengan dasar-dasar yang sangat kuat, dan mampu memberikan jalan tengah antara Islam dan isu-isu yang berkaitan dengannya. 38 Iip D. Yahya, Gus Dur: Berbeda Itu Asyik (Yogyakarta: Kanisius, 2008), Cet. Ke-5, h. 60. Djohan Efendi, “Gus Dur: Sang Presiden yang Humanis,” dalam Ahmad Gaus AF, Sang Pelintas Batas: Biografi Djohan Efendi (Jakarta: ICRP, 2009), h. 191. 40 Hanif, 41 Warisan Kebesaran Gus Dur, h. 30. 39 23 Respon-respon Gus Dur kemudian memberikan kemantapan hati umat Islam untuk tetap tidak gentar menghadapi arus globalisasi. Karena mereka sudah menemukan jalan terbaik untuk dilalui di tengah hantaman arus budayabudaya dunia yang siap mengikis ajaran dan budaya mereka. Gus Dur juga menunjukkan suatu sikap yang benar-benar terbuka terhadap segala di luar Islam tanpa harus menghilangkan hakikat Islam itu sendiri. Tetapi dengan catatan selama apa yang ada di luar Islam itu dapat memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat manusia. Pemikiran-pemikiran Gus Dur tidak hanya diterima di kalangan umat Islam Indonesia, tetapi pemikirannya sudah mewakili pemikiran Islam dalam menyuarakan pemikiran-pemikiran cemerlang yang menjadi perhatian intelektual dunia. Bukti diterima pemikirannya di kancah pemikiran internasional ialah banyaknya penghargaan internasional yang diteriman Gus Dur.41 Bahkan Gus Dur tidak hanya berteori, ia juga tidak segan-segan memperaktekkan teori tersebut dalam kehidupan nyata. Dalam wacana Hak Asasi Manusia, Gus Dur tidak hanya memberikan konsep-konsep kosong mengenai pembelaan HAM, tetapi ia juga mengaplikasikan dalam kehidupan nyata. Misalkan pembelaan terhadap hakhak kaum Konghucu yang terpasung selama Orde Baru. Atas kerja keras tersebut Gus Dur mendapatkan penghargaan dari sebuah yayasan yang bergerak di bidang penegakan Hak Asasi Manusia, Simon Wiesenthal Center, dan dri 41 Mohammad, Gus Dur, h. 54-55. 24 Mebal Valor.42 Bahkan pemikiran-pemikiran yang cemerlang dan langkahlangkah yang mencengangkan itu juga mendapatkan perhatian dari Universitas Tampel. Dan namanya diabadikan sebagai nama kelompok studi Abdurrahman Wahid Chair of Islamic Study.43 Keluasan cakrawala keilmuannya yang melintasi ilmu agama serta kepiawayannya memanfaatkan ilmunya untuk memberikan solusi-solusi kreatif mengenai seluruh aspek permasalahan-permasalahan umat merupakan keunggulan Gus Dur yang patut dijuluki sebagai pendekar intelektual yang handal. Bahkan sampai saat ini tampaknya belum ada tokoh Islam yang mampu menggantikan posisi tersebut. B. Murtadlâ Muthahharî 1. Riwayat Hidup Murtadlâ Muthahharî merupakan putra dari seorang ulama terkemuka dan dihormati, Syekh Muhammad Husain Muthahharî.44 Muhammad Husain adalah orang pertama yang memperkenalkannya dengan ilmu pengetahuan. Ia berada di bimbingan ayahnya sampai 12 tahun setelah kelahirannya.45 Kelahirannya bertepatan pada 2 Februari 1920 M yang bertepatan dengan 12 Jumadil Ula 1228 H di Fariman.46 42 Abdurrahman Wahid, http://id.wikipedia.org. Ibid. 44 Haidar Baqir, Murtadlâ Muthahharî, Sang Mujahid Sang Mujahid (Bandung: Yayasan Muthahharî, 1998), h. 25. 45 Syamsuri, “Manusia Sempurna Perspektif Murtadlâ Muthahharî” (Laporan Penelitian Dosen Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2001), h. 8. 46 Haidar, Murtadlâ Muthahharî, h. 26. 43 25 Bekal ilmu keagamaan pertamakali didapatkan dari ayahnya. Sehingga sang ayah bukan hanya sekedar orang tua darinya, tetapi juga menjadi seorang guru yang sangat mempunyai perhatian yang cukup tinggi terhadap pendidikannya, sehingga ia selalu membimbingnya dengan baik. Sedangkan keilmuan tentang membaca, menulis, surat-surat pendek al-Qur‟an dan pengentar sastra Arab didapatkan dari madrasah di Fariman tempat ia belajar.47 Tampaknya, ilmu-ilmu yang didapatkan itulah yang kemudian menjadi bekal dan bahkan mampu memengaruhi perkembangan intelektualnya. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar tersebut, ia kemudian berpetualang ke Hawzah Masyhad untuk melanjutkan studi keagamaannya. Tempat itu adalah pusat pendidikan agama Syi‟ah. Di Hawzah Masyhad tersebut, Muthahharî telah menunjukkan kecerdasan dan keseriusan dalam upaya mempelajari ilmu-ilmu Islam. Di sana, beliau juga telah menunjukkan minat besar terhadap filsafat dan Irfan. Selama di Masyhad, beliau banyak terinspirasi oleh kepribadian seorang filsuf Islam tradisional ternama kala itu, Mirza Mehdi Syahidi Razavi.48 Tepatnya pada 1936, ia pindah ke Qom untuk memperdalam ilmu keagamaan. Di tempat tersebut, ia belajar di bawah bimbingan Ayatullah Boroujerdi dan Khomeini.49 Tentunya kepindahan tersebut berlasan yang kuat. 47 Dewan Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 313. 48 Muhsin Labib, Filosof Sebelum dan Sesudah Mulla Shadra (Jakarta: Lentera, 2005), h. 278. Jamaluddin Rahmat, “Kata Pengantar,” dalam Murtadlâ Muthahharî, Perspektif al Qur’an tentang Manusia dan Agama (Bandung: Mizan, 1992), h. 8. 49 26 Di antara faktor-faktor yang menjadikannya pindah ialah pertama, guru yang menjadi curahan perhatiannya, Mirza Mehdi Syahidi Razawi wafat pada tahun 1936. Kedua, Kemunduran yang dialami Hawzah Masyhad. Ketiga, adanya tekanan-tekanan destruktif dari pemerintah tirani yaitu raja Reza Khan, terhadap seluruh lembaga-lembaga ke-Islam-an, termasuk Hawzah Mashyad.50 Kerajaan Persia kala itu menganggap bahwa eksistensi berbagai institusi Islam tersebut dapat mengganggu stabilitas politis negara.51 Khomeini merupakan guru yang mempunyai hubungan yang sangat dekat dengannya. Sang imam adalah pengajar muda yang mempunyai kedalaman dan keluasan wawasan keislaman dan kemampuan menyampaikannya kepada orang lain dengan sangat baik. Kehebatannyalah yang menjadikan pelajaran-pelajaran khomaeni terutama pelajaran mengenai irfannya meninggalkan bekas yang amat kuat dalam hati Muthahharî. Bahkan materi yang disampaikan Khomaeni itu masih terngiang-ngiang di telinganya sampai beberapa hari setelah mendengarkannya. Tidak hanya Khomaeni yang menjadi gurunya. Bahkan ʻAllamah Thabatthabaʻî yang juga merupakan ulama besar di masanya juga menjadi guru favoritnya di bidang filsafat dan irfan. Sedangkan pemikiran ʻAllamah juga dipengaruhi kajian-kajian mengenai Nahj al-Balâghah. Nahj al-Balâghah 50 51 155-156. Muhsin, Filosof, h. 279. Murtadlâ Muthahharî, Mutiara Wahyu, terj. Syekh Alî al-Ḥamîd (Bogor: Cahaya, 2004), h. 27 merupakan kumpulan wacana, pidato, surah-surah dan kata-kata bijak khalîfah keempat dan imam pertama dalam madzhab Syi‟ah, „Alî bin Abî Thâlib.52 Pada tahun 1950 Murtadlâ konsentrasi lebih keras lagi pada studi filsafat. Ia meneruskan bacaannya tentang Marxisme melalui terjemahan Persia dari karya George Pulizer yang berjudul Introduction to Philosophy dan mulai mengikuti diskusi Kamis Thabatthabaʻî tentang “filsafat materealis.” Diskusi ini berlangsung dari tahun 1950-1953 dan menghasilkan lima jilid buku Ushule Falsafah va Ravesh-e Realism (Prinsip-prinsip Filsafat dan Metode Realistik). Murtadlâ kemudian mengedit karya ini dan menambahkan catatan-catatan yang luas (lebih besar dari naskah aslinya sendiri) dan secara bertahap menerbitkannya (1953-1985). Di samping itu pada waktu ini ia mempelajari Ibn Sina dengan Thabatthabaʻî. Di antara teman kelasnya adalah Muntazeri dan Behesti Mengenai Nahj al-Balâghah, selain dikenal merupakan suatu model ketinggian sastra Arab, seperti antara lain diungkapkan oleh Syaikh Muḥammad „Abduh, kitab ini berisi banyak ungkapan-ungkapan teologis, filosofis, dan mistis yang amat sophisticated. Dari kitab ini (di samping ucapanucapan para imam lain) kaum Syi‟ah menggali banyak dasar-dasar filsafat dan irfan. Inkorporasi Nahj al-Balâghah ke dalam sistem Filsafat Islam yang berkembang di Iran diketahui mencapai puncaknya pada aliran Hikmah Mullah Shadra. Untuk sekedar mengetahui isinya, khususnya yang menarik minat 52 Haidar Baqir, Membincang Metodologi Ayatullâh Murtadlâ Muthahharî (Yogyakarta: UGM, 2004), h. 2. 28 Muthahharî, berikut ini adalah topik-topik yang terutama dibahas kitab ini Muthahharî dalam karyanya yang berjudul Sayr’e dar Nahu al- Balâghah (pelancangan dalam Nahj al-Balâghah). Teologi dan metafisika, suluk (tasawuf) dan ibadah, kuliah-kuliah mengenai akhlak, serta dunia dan keduniaan (dalam hubunganya dengan sikap seseorang arif dan sufi terhadapnya). Dari kesemuanya di atas itulah yang membentuk dasar karakter pola pikir Muthahharî menjadi seorang pemikir Syiʻî yang dapat memadukan antara filsafat dan agama serta menanggapi setiap persoalan secara rasionalitas dan filosofis, sebagaimana di dalam Sya‟ir dan Nahj al-Balâghah, misalnya Murtadlâ membantah pernyataan sebagian pengamat yang menyatakan bahwa rasionalisme dan kecendrungan kepada filsafat lebih merupakan pengaruh budaya intelektual Persia dari pada budaya intelektual ke-Islam-an. Dia menunjukkan bahwa semuanya itu berada di jantung ajaran Islam, sebagaimana ditunjukkan oleh al-Qur‟an, Hadis nabi dan ajaran para imam. 2. Karya-Karya Murtadlâ Muthahharî cukup produktif dalam menghasilkan karya. Ia mempunyai karya yang cukup banyak, yaitu sekitar enam puluhan. Tulisan tersebut terdiri dari tulisan sendiri dan juga banyak akumulasi dari pidatopidatonya yang kemudian diterbitkan menjadi buku. Di antara buku-buku yang telah diterbikan ialah al-ʻAdl al-Ilâhi, buku ini menjelaskan tentang konsep keadilan, baik keadilan Ilahi maupun keadilan 29 manusia. Bis Guftôr, buku ini merupakan kumpulan 20 ceramah yang secara keseluruhan mengacu pada pembahasan mengenai keadilan, hak-hak, ilmu, akal, hati dan tentang cara berpikir yang ideal dalam kehidupan. Fundamentals of Islamic Thought God, Man and Universe, buku ini menjelaskan tentang persoalan Tuhan, manusia dan alam semesta. Goal of Life. Buku ini menjelaskan tentang tujuan penciptaan, landasan etika personal dan etika sosial, agama, madzhab pemikiran dan pendangan dunia Islam serta proses penyempurnaan manusia serta tauhid Islam. Hak wa al-Bathil, buku ini menjelaskan nilai-nilai pandangan dunia ideologi Islam di hadapan pandangan dunia dan ideologi lain, buku ini memberikan tawaran pemikiran alternatif tentang kebenaran dan kebatilan, plus sebagai kritik yang jitu terhadap berbagai penyelewengan pemikiran yang sedang berkembang. Inna al-Dîn ‘Inda Ilâh al-Islâm, buku ini menjelaskan tentang cara melihat kebenaran ajaran Islam yang murni sebagai bentuk filsafat sosial dan keyakinan ketuhanan, pola pikir dan kepercayaan yang konstruktif dan konfrehensif. Dan cara mengenal kondisi umat Islam harus senantiasa cemat melihat orientasi perkembangan sains dan pengetahuan, mana fenomena yang menyimpang, imam yang sebenarnya secara substansial harus dikembangkan. Insône Kômil, buku ini menjelaskan tentang hakikat manusia. Yang menurutnya manusia hakiki itu adalah manusia multi dimensional dengan melaksanakan seluruh ajaran potensi kemanusiaannya dengan utuh dan 30 harmonis. Buku ini merupakan ceramahnya yang disampaikan pada bulan Ramadhan. Introduction to Kalam, buku ini membahas tentang ilmu kalam yang merupaka ilmu yang mengaji mengenai dasar-dasar pokok aqidah seseorang terhadap teologi. Man and Universe, buku ini merupakan akumulasi poin-poin penting tentang berbagai problematika manusia dan alam semesta yang diimbangi dengan argumentasi yang ilmiah, filosofis, logis serta merujuk kepada al-Qur‟an. Mas’alê-ye Syenôkh, buku ini merupakan kumpulan ceramahnya tentang penguatan landasan filsafat Islam yang pada waktu itu penganut Marxisme melakukan aktifitas besar-besaran di bidang kebudayaan. Penguatan itu dengan cara memperbaiki kerangka pemikiran umat Islam dalam ranah epistemologis yang mengarahkan pada hakikat epistemologi Islam. Ceramah itu disampaikan pada bulan Muharram 1397 H/1977 M. Perspektif al-Qur’an tentang Manusia dan Agama, buku ini menjelaskan menenai tiga persoalan pokok yaitu manusia dan keimanan, manusia menurut al-Qur‟an, manusia dan takdirnya. 3. Kedudukan Murtadlâ Muthahharî dalam Pemikiran Islam Murtadlâ adalah pemikir yang mengabdikan hidupnya untuk perjuangan ideologi dan politik.53 Selain itu ia merupakan seorang cendekiawan muslim yang mempunyai pengetahuan dan wawasan mendalam tentang berbagai hal. 53 h. 56-58. Haidar Bagir, Murtadlâ Muthahharî Sang Mujahid (Bandung: Yayasan Muthahharî, 1988), 31 Syamsuri menyebutkan bahwa ia adalah intelektual muslim yang taat beragama, moderat, dan terbuka dan senantiasa berkeinginan mengembangkan dan memperluas wawasan berpikir generasi muda Islam Iran dan meningkatkan kualitas pendidikan mereka.54 Beliau adalah seorang filosof besar yang tidak hanya menguasai filsafat Islam, namun juga filsafat Barat. Meskipun ia juga menguasai filsafat Barat, tetapi ia tetap menjadi cendikiawan yang sangat gagah dan tidak pernah rendah diri terhadap ilmuwan Barat, bahkan ia tidak malu untuk mengutip pemikiranpemikiran ilmuwan Islam. Tidak sama dengan kebanyakan ilmuan yang merasa rendah diri dihadapan pemikir barat sehingga kemudian ia memuja pemikiran Barat tanpa berpikir kritis terhadapnya. Dari pemikiran dan metodologi yang beliau gunakan, Murtadlâ termasuk dalam kategori pemikiran Islam atau islamic thought (al-fikr alislâmî). Beliau sudah menggunakan metode dan pendekatan dalam pemikirannya, namun di samping itu juga beliau masih berada dalam lingkaran sebagai seorang muslim yang taat terhadap agama Islam sekte Syi‟ah, sebagai agama yang beliau anut sejak kecil. Tidak heran, karena memang sejak dini ia sudah memperlihatkan kecenderungan yang kuat pada filsafat Islam. Kecenderungannya itu dipicu oleh pandangannya tentang filsafat sebagai senjata ideologi yang ampuh untuk menghadapi ide-ide sekular yang tersebar cepat di Iran pada waktu itu. 54 Syamsuri, “Manusia Sempurna Perspektif Murtadlâ Muthahharî”, h. 15. 32 Dari aspek pemikiran, Muthahharî memang tidak kalah intelektualnya dengan ilmuan barat yang terkenal seperti Sartre, Heidegger atau Buber. Karena dalam pemikiran mengenai eksistensi manusia dan alam, Muthahharî sudah melakukan permenungan yang aktif dan menyajikannya dengan sangat kritis dan analitis.55 Sedangkan dalam ranah filosof muslim, ia disamakan dengan alGhazâlî. Kesamaannya terletak pada kecenderungannya melihat filsafat sebagai senjata ampuh ideologi untuk menangkal ide-ide filosofis. Tetapi perbedaannya ialah terletak lawan yang dihadapinya. Kalau al-Ghazâlî menghadapi ide-ide filosofis para filosof muslim yang dianggap tidak ortodoks. Sedangkan yang dihadapi Muthahharî ialah ide-ide sekular Barat, khususnya Marxisme. Tetapi keduanya mempunyai semangat yang sama.56 Dalam mengkritik ideologi Marxisme, Muthahharî sampai pada satu kesimpulan bahwa ideologi Marxisme tidak sesuai dengan ideologi Islam, sehingga tidak pantas bagi ummat untuk mengusung ideologi tersebut. Memudahkan memahami argumentasi yang dipakainya, Muthahharî mengajukan diagram di bawah ini. Epistemologi --> Paradigma --> Ideologi --> Praktik Diagram di atas menjelaskan relasi antara ideologi dengan paradigma (worldview) seseorang ibarat fondasi dasar sebuah bangunan dengan bagian 55 Jalaluddin Rahmat, “Mutahhari: Sebuah Model Buat Para Ulama‟,”, h. 8. Mulyadi Kartanegara, Renungan-renungan Filosofis Murtadlâ Muthahharî (Makalah Seminar Internasional Pemikiran Murtadlâ Muthahharî di Auditorium Adhiyana Wisma Antara lt.2, 2004), h. 4. 56 33 atas bangunan tersebut. Singkatnya, ideologi sebagai hikmat amali (ilmu praktis) mesti berlandaskan pada hikmat nazhari (ilmu teoritis) tertentu.57 Tetapi menurut Ḥamîd Dabbashî -sebagaimana diungkapkan Mulyadi Kartanegara dalam makalahnya- bahwa sumber-sumber yang dipakai Muthahharî untuk mempelajari Marxisme ini adalah sekunder, yaitu sumbersumber yang bisa ia dapatkan dalam bahasa Persia, baik pamplet-pamplet oleh kaum Marxis yang tergabung dalam partai Tudeh, atau terjemahan karya Marx ke dalam bahasa Persia atau sumber Arab berbahasa Arab.58 Selain itu, Murtadlâ merupakan salah satu tokoh yang memberikan perhatian yang serius terhadap filsafat. Menurutnya filsafat mempunyai peran penting dalam pertempuran ideologi. Ia merupakan senjata ideologi, sehingga Muthahharî berusaha menghidupkan kembali tradisi filosofis, dan ia percaya filsafat merupakan prioritas utama dalam skala makna di antara semua cabang ilmu pengetahuan. Maka dari itu Murtadlâ dikenal sebagai pemikir filosofis juga dikenal sebagai salah seorang tokoh pembela kebebasan berpikir. Muthahharî berkeyakinan bahwa eksistensi Islam tidak bisa dipertahankan kecuali dengan kekuatan ilmu dan pemberian kebebasan terhadap ide-ide yang muncul. Oleh karena itu, ajaran Islam yang dipercayai dan diyakini kebenarannya harus melindungi kebebasan berpikir. 57 Haidar Bagir, Resensi Buku Murtadlâ Muthahharî : Pengantar Epistemologi Islam: Sebuah Pemetaan dan Kritik Epistemologi Islam atas Paradigma Pengetahuan Ilmiah dan Relevansi Pandangan Dunia (Jakarta: Sadra Press, 2010), h. ii. 58 Mulyadi, Renungan-Renungan Filosofis Murtadlâ Muthahharî, h. 2. 34 Filsafat bagi Muthahharî merupakan alat dan metode untuk memahami ajaran-ajaran Islam, di samping untuk mempertahankan diri dari pengaruh ideologi-ideologi yang menyimpang. Tetapi, menurut Muthahharî, filsafat bukan merupakan kebenaran yang berdiri sendiri, di sampingnya, ada kebenaran agama. Kebenaran filsafat dan kebenaran agama, bagi Muthahharî tidak saling bertentangan. Berdasarkan keyakinan ini, Muthahharî selalu mendasarkan pemikirannya pada kebenaran-kebenaran agama, kemudian dipahami, diinterpretasikan, dan dipertahankan dengan kebenaran-kebenaran filosofis. Muthahharî memandang serbuan pemikiran Barat sebagai musuh terbesar dari pemikiran Islami. Menghadapi pertempuran intelektual ini menurut Muthahharî harus dengan menggunakan senjata intektual pula. Muthahharî tidak menolak Barat dengan mengumumkan shalat istikharah, tidak pula dengan menyesuaikan ajaran Islam pada kerangka pemikiran Barat (seperti kaum modernis yang membungkus paham Barat dengan kemasan Islam). Muthahharî mengadakan penelitian tentang dasar-dasar pemikiran yang sudah terbaratkan; Ia mengkaji dan menyangkal secara rasional aliran-aliran filsafat intelektual dan sosial Barat dan memberikan interprestasi baru tentang pemikiran dan praktik-praktik keislaman secara logis dan rasional.59 59 Seyyed Hossein Nasr, Islam Tradisi di Tengah Kancah Dunia Modern, terj: Luqman Hakim (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994), Cet. Ke-1, h. 195. BAB III FILSAFAT MANUSIA DALAM PANDANGAN ABDURRAHMAN WAHID DAN MURTADLÂ MUTHAHHARÎ A. Filsafat Manusia menurut Abdurrahman Wahid 1. Mengenai Hakikat Manusia Konsep tentang hakikat manusia merupakan pemikiran fundamental Gus Dur dalam memberikan apresiasi luas terhadap segala hal, baik dalam kehidupan manusia dan dalam memberikan perhatian pada kesejahteraan setiap individu. Tampaknya Gus Dur memang benar-benar memposisikan manusia pada tempat yang sebenarnya. Terbukti dalam setiap langkahnya Gus Dur selalu mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan. Menurutnya, manusia adalah satu-satunya makhluk yang mempunyai kesempurnaan keadaan yang paling tinggi dalam setiap ciptaan Tuhan. Ia adalah makhluk yang dilengkapi akal, perasaan dan keterampilan untuk mengembangkan diri. Segala kelengkapan itu tidak dimiliki makhluk lainnya.63 Demikianlah manusia lebih unggul dari makhluk lainnya. Ditinjau dari aspek ini, sesungguhnya seluruh manusia memiliki kedudukan yang tinggi dalam tatanan kosmologi sehingga setiap individu harus memperoleh perlakuan dan hak-hak dasar yang sama.64 Karena posisi manusia yang tinggi itu menuntut pula penghargaan kepada nilai-nilai dasar kehidupan 63 Abdurrahman, Islam Kosmopolitan, h. 30. Samsul Bakri dan Udhofir, Jombang-Kairo, Jombang Chicago: Sintesis Pemikiran Gus Dur dan Cak Nur dalam Pembaharuan Islam di Indonesia (Solo: Tiga Serangkai, 2004), Cet. Ke-1, h. 49. 64 35 36 manusia yang sesuai dengan martabatnya. Hal itu menuntut agar manusia dipandang sebagai manusia. Hak-hak dasar itu tidak lain ialah nilai-nilai dasar manusia. Nilai-nilai dasar manusia merupakan dimensi-dimensi kemanusiaan yang memang sudah melekat dalam diri manusia sejak lahir. Adapun dimensi-dimensi yang dimaksud ialah dimensi materi, keyakinan, moralitas, kepemilikan, kreativitas65 dan rasionalitasnya. 66 Apa yang disebutkan tadi merupakan dimensi-dimensi kemanusian yang bersifat universal, karena setiap individu pasti mempunyai dimensi-dimensi itu. Melekatnya fitrah dalam diri manusia, menjadikan manusia berbeda dengan makhluk lainnya. Dalam artian, fitrahnya menjadikan manusia sebagai makhluk termulia di jagat raya. Untuk menjadi manusia seutuhnya, manusia harus memberikan ruang gerak yang cukup bagi dirinya sendiri di luar dan di dalam dirinya sendiri.67 Maka dari itu dimensi-dimensi tersebut harus dilindungi demi lahirnya kebebasan dimensi-dimensi manusia dalam rangka perkembangan hidup manusia yang optimal. Kebebasan tersebut menjadikan manusia dapat mengembangkan pemikiran dan kepribadiannya tanpa intervensi dari luar baginya.68 Jika kalau tidak demikian, manusia sebagai individu cenderung 65 Abdurrahman Wahid, Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan (Depok: Desantara, 2001), Cet. Ke-2, h. 180. 66 Abdurrahman, Islam Kosmopolitan, h. 8-11. 67 Ibid, h. 36 68 Wawan Kurniawan, “Menolak HAM atau Mengubah Fiqh?: Pemikiran Gus Dur tentang Islam dan HAM,” Kajian Kebudayaan dan Demokrasi, Weltanscauung Gus Dur, Edisi. vi (Juni 2010), h. 40. 37 memperlakukan dirinya secara berlebihan. Akibatnya, kebebasan keakuan manusia justru akan mengganggu manusia lainnya dalam meraih hakikatnya sebagai manusia. Kebebasan manusia bukan kebebasan tanpa batas. Tetapi kebebasan manusia yang dimaksud Gus Dur tidak lain ialah kebebasan yang dibatasi oleh kebebasan manusia lainnya. Itulah yang disebut Gus Dur sebagai kebebasan yang dilandaskan pada dimensi-dimensi kemanusiaan. Hal tersebut harus tumbuh dari hati nurani manusia. Karena kesadarannya akan hakikat manusia itu sendiri merupakan hal yang sangat penting demi terciptanya saling menghargai di antara sesama manusia.69 Sartre membahasakan dengan kebebasan yang juga harus memerhatikan kebebasan orang lain, yang oleh Sartre diistilahkan dengan kata Faktisitas.70 Manusia yang mampu menerapkan penghargaan kepada sesama, pada dasarnya ia sadar bahwa setiap manusia terlahir dalam keadaan mulia. Ia terlahir dalam keadaan dibekali dimensi-dimensi dasar yang sangat manusiawi. Tetapi dalam kehidupannya, terkadang manusia sendiri justru melupakan dimensi-dimensi kemanusiaan tersebut. Jika manusia dapat memahami dan melaksanakan dimensi-dimensi tersebut dengan baik dalam kenyataan, 69 Abdurrahman Wahid, “Pengembangan Ahlussunah wal Jama’ah di Lingkungan Nahdlatul Ulama”, dalam Said Aqil Siradj, Ahlussunnah wa al-Jamaʻah: Sebuah Kritik Historis (Jakarta: Pustaka Cendekia Muda, 2008), Cet. Ke-1, h. viii. 70 Lili Tjahjadi, “Ateisme Sartre: Menulak Tuhan Mengiyakan Manusia,” dalam Filsafat Eksistensialisme Jean-Paul Sartre (Yogyakarta: Kanisius, 2003), Cet. Ke-3, h. 131. 38 sesunggunya manusia yang demikian merupakan manusia yang sempurna, manusia yang sesuai dengan hakikat dirinya sebagai manusia yang mulia.71 Kemuliaan manusia dilengkapi oleh Allah dengan firman-Nya pula dalam surat al-Tîn/95: 4, yaitu, “laqad khalaqnâ al-insâna fî aḥsani taqwîm” (“sesungguhnya telah Ku-jadikan manusia dalam bentuk kemakhlukan yang sebaik-baiknya”) dan dengan keseluruhan peranan status dan bentuk kemakhlukan itu manusia dijadikan Allah sebagai pengganti-Nya di muka bumi (khalîfatullâh fî al-ardl).72 Fitrah manusia yang diterangkan di atas merupakan anugerah dari Allah kepada manusia agar manusia mampu menjalankan tugasnya sebagai khalîfahNya. Kepercayaan Tuhan akan diri manusia merupakan derajat yang sangat spesial yang tidak satu pun makhluk lain mendapatkannya. Jabatan itu menjadikan manusia sebagai satu-satunya makhluk yang mempunyai posisi tertinggi ke-2 setelah Tuhan. Tuhan tidak akan pernah salah pilih dalam menentukan suatu pilihan, termasuk juga dalam memilih manusia untuk menjadi pengganti-Nya di muka bumi. Menurut Gus Dur, Tuhan memilih manusia sebagai pengganti-Nya tidak lain karena dalam penciptaannya, manusia dibekali berbagai potensi yang dimungkinkan dapat mengemban tugas berat tersebut. Diutusnya manusia mempunyai tugas-tugas utama. Dalam suatu tulisan, Gus Dur mengatakan bahwa tugas utama manusia sebagai khalîfah tidak lain ialah untuk membawakan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Sebagaimana Nabi Muhammad diutus Allah untuk kesejahteraan manusia. 71 72 Abdurrahman, Islam Kosmopolitan, h. 368-369. Abdurrahman, Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan, h. 153. 39 Pesan-pesan yang dibawakan Islam pada umat manusia adalah sederhana saja: bertauhid, melaksanakan syariah, dan menegakkan kesejahteraan di muka bumi. Kepada kita telah diberikan contoh sempurna, yang harus kita teladani sejauh mungkin, yaitu Nabi Muhammad Saw. Hal itu dinyatakan dalam al-Qur’an surat al Aḥzab/33: 21, yaitu “laqad kâna lakum fî rasûlillâh uswatun ḥasanah” (“telah ada bagi kalian keteladanan sempurna dalam diri Rasulullah”). Keteladanan itu tentunya paling utama terwujud dalam peranan beliau untuk membawakan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia (raḥmatan li’al-âlamîn). Karena meneladani peranan pembawa kesejahteraan itulah manusia diberi status tinggi di hadapan Allah, seperti firman-Nya dalam surat al-Isra’/17: 70, yaitu, “laqad karramnâ banî âdam” (“sungguh telah Ku-muliakan anak Adam”).73 Dalam teks di atas, Gus Dur ingin menjelaskan bahwa urutan pesan yang dibawakan Islam merupakan suatu urutan menuju pada kesempurnaan manusia sebagai khalîfah Tuhan. Bertauhid merupakan menjadi modal utama yang harus tertanam dalam diri manusia untuk menjadi diri yang sempurna. Kebertauhidan manusia mendorongnya untuk menjalankan syariah yang dihasilkan dari persaksian manusia akan Tuhan. Maka menjalankan syariah merupakan suatu tanda bahwa seseorang itu bertauhid. Tidak hanya itu, kebertauhidan dan melaksanakan syariah itu pula mendorong manusia untuk berbuat sebagaimana perintah Tuhan yaitu menciptakan kesejahteraan untuk alam semesta. Seseorang yang bertauhid dan melaksanakan syariah dengan baik dan benar sudah merupakan kepastian baginya untuk terus berusaha memakmurkan dan menyejahterakan seluruh jagat raya. Sehingga seseorang yang tidak menyebarkan rahmat berupa kesejahteraan tidak dapat dikatakan sebagai manusia yang bertauhid dan melaksanakan syariah. 73 Ibid, h. 153. 40 Dengan demikian, Gus Dur menempatkan kesejetahteraan sebagai ukuran hakikat manusia itu sendiri. Sedangkan unsur-unsur dasar kemanusiaan merupakan modal awal yang sangat penting untuk menuju pada derajat tertinggi manusia. Derajat tertinggi manusia ialah jika ia mampu memanfaatkan dimensi-dimensi manusia demi kesejahteraan umat manusia. Manusia yang nilai-nilai kemanusiaannya berkembang dengan seimbang ialah dia yang menyejahterakan seluruh umat manusia. Maka itulah hakikat manusia, yang seharusnya menjadi cita-cita seluruh umat manusia agar dirinya mampu menjadi manusia yang sesungguhnya. Gus Dur tidak hanya menyusun teori tentang hakikat manusia. Tetapi ia juga memberikan contoh yang sangat baik mengenai teorinya tentang manusia yang sebenarnya. Gus Dur tidak ragu-ragu menggunakan segala kekuatannya untuk kesejahteraan manusia. Ketika menjadi presiden, kesejahteraan masyarakat menjadi perjuangan utamanya. Saking pedulinya pada kesejahteraan, Franz Magnis Suseno SJ menyamakan Gus Dur dengan para khalîfah Mongul yang memang benar-benar bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kebahagiaan minoritas yang hidup di bawah pemerintannya.74 2. Dimensi-dimensi Manusia Terdapat beberapa dimensi yang menurut Gus Dur harus diasah jika manusia ingin menjadi diri yang sesungguhnya. Dimensi-dimensi itulah yang 74 Franz Magnis Suseno, “Gus Dur: Bangsa Mana di Dunia Mempunyai Presiden seperti Kita,” dalam Gila Gus Dur: Wacana Pembaca Abdurrahman Wahid (Yogyakarta: LKIS, 2000), Cet. Ke-1, h. 21. 41 akan benar-benar menampilkan kesempurnaan manusia dibandingkan makhluk lainnya. Dimensi-dimensi itu ialah dimensi badani, keyakinan, moralitas, kepemilikan, kreativitas dan rasionalitasnya. Manusia berposisi sebagai makhluk yang terdiri dari aspek materi, yaitu susunan fisik yang disebut tubuh. Aspek materi manusia merupakan suatu alat untuk merealisasikan segala apa yang ada dalam pikiran dan hati seseorang. Dengan demikian, untuk mengoptimalkan potensi ini, individu harus mampu mengembangkan persamaan hak dan derajat antarsesama manusia.75 Persamaan hak dan derajat akan melahirkan saling menghormati segala potensi manusia antarsesama yang memang harus memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan segala pontensinya. Selain dimensi materi, manusia juga mempunyai dimensi keyakinan yang memang sudah melekat dalam diri manusia. Keyakinan inilah yang memungkinkan manusia untuk mendekat dan menemukan Tuhannya. Sehingga menangkap eksistensi Tuhan itu oleh Gus Dur disebut sebagai bagian dari fitrah manusia. Hal tersebut yang menjadikan Gus Dur tidak ragu untuk mengatakan bahwa manusia dituntut memiliki landasan berupa bekal keyakinan yang kuat,76 karena hal itu merupakan bagian dari penyempurna hakikat diri manusia itu sendiri. 75 Abdurrahman, Islam Kosmopolitan, h. 5. Abdurrahman Wahid, Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren (Yogyakarta: LKIS, 2007), Cet. Ke-2, h. 184. 76 42 Dalam tatanan alam, sebenarnya manusia mempunyai posisi yang sangat unik, yaitu keberadaannya di antara alam semesta dan Tuhan. 77 Sebagai makhluk yang berkeyakinan yang merupakan bagian dari rohani, manusia mempunyai potensi untuk menangkap pesan-pesan dari Tuhan. Sebagai makhluk materi kemudian manusia menyampaikannya atau mengaplikasikannya kepada alam semesta.78 Manusia ibarat suatu jembatan yang menjadi perantara yang amat baik untuk menyatukan alam semesta dengan Tuhan. Sehubungan dengan hal tersebut, Gus Dur menambahkan bahwa sebagian dari unsur dasar manusia ialah hakikatnya sebagai makhluk bermoral. Moral oleh Gus Dur diartikan sebagai kerangka etis yang utuh maupun dalam arti kesusilaan.79 Dimensi moralitas ini yang oleh Gus Dur disebut sebagai landasan keimanan yang memancarkan toleransi dalam derajat sangat tinggi.80 Dimensi moral ini merupakan suatu bekal manusia dalam hidup berdampingan dengan manusia lainnya. Konsep mengenai manusia sebagai makhluk bermoral, Gus Dur juga mengambilnya dari kandungan al-Qur’an yang banyak menyatakannya. Ayat yang menyatakan manusia sebagai makhluk yang berbangsa dan bersuku-suku merupakan salah satu yang menjelaskan tetang aspek moralitas manusia.81 77 R.A. Nicholson, Tasawuf Cinta: Studi atas Tiga Sufi: Ibn Abî al-Khair, al-Jîlî dan Ibn alFarid, terj. Uzair Faizan (Bandung: Mizan, 2003), h. 144. 78 Mulyadhi Kartanegara, Nalar Religius: Memahami Hakikat Tuhan, Alam dan Manusia (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 12. 79 Abdurrahman, Islam Kosmopolitan, h. 6. 80 Abdurrahman, Islam Kosmopolitan, h. 6. 81 Abdurrahman, Islamku, Islam Anda, Islam Kita, h. 25. 43 Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Hujarat/49: 13 yakni “wa jaʻalnâkum syuʻûban wa qabâila litaʻârafû” (“Dan Ku-jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa agar saling mengenal”). Dimensi moralitas ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan sosial manusia. Manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain.82 Antara yang satu dengan yang lainnya terjadi hubungan timbal balik yang saling membutuhkan demi serangkaian penemuan identitasnya untuk meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri.83 Dengan demikian, kehidupan sosial manusia membutuhkan pengakuan manusia pada eksistensi manusia yang lain. Sehingga perbedaan tiap individu harus diakui mempunyai kebebasan yang sama. Karena mempunyai kebebasan yang sama dalam tiap individu, sehingga dibutuhkan saling menghormati antara kebebasan yang satu dengan yang lainnya. Hubungan yang baik itu akan melahirkan perkembangan segala potensi dalam dirinya. Inilah bentuk pengabdian diri manusia terhadap sesama. Menurutnya, hasrat mengabdikan diri kepada sesama merupakan suatu hal yang harus dipupuk dalam hubungannya dengan sesama.84 Syamsul Bakri dan Mudhofir mengungkapkan dengan sangat baik dalam bukunya mengenai pemikiran Gus Dur tentang manusia sebagai makhluk bermoral. Bagi Abdurrahman Wahid, penanggulangan kemiskinan harus dilakukan dengan mendudukkan martabat manusia pada tempat yang tinggi, yaitu 82 Ibid, h. 161. Abdurrahman Wahid, Prisma Pemikiran Gus Dur (Yogyakarta: LKIS, 2010), h. 90. 84 Hamdan, Dari Teologi Profesional ke Teologi Praktisi, h. 131. 83 44 sebagai makhluk bermoral dengan hak-hak asasi dan kebutuhannya sendiri.85 Dalam kutipan di atas, dinyatakan bahwa Gus Dur memosisikan manusia sebagai makhluk yang sangat tinggi ketika manusia mampu hidup dengan sesama, dengan segala pemenuhan seluruh haknya sebagai manusia yang utuh. Jika hal tersebut tidak dicapai, manusia tidak dapat dikatakan sebagai manusia, melainkan hanyalah bayangan mengenai manusia. Adelbert Snijders juga mengungkapkan mengenai pentingnya manusia hidup dalam suatu interaksi dengan sesama. Menurutnya, manusia tidak akan pernah menjadi manusia sampai ia hidup bersama manusia pula. Kebersamaan hidup manusia tersebut juga akan menjadikan dunia sebagai tempat yang manusiawi.86 Tetapi hidup manusia bersama dengan manusia lainnya tidaklah cukup menjadikannya sebagai makhluk yang unggul. Terdapat hal lain yang juga melengkapi keunikan manusia sebagai makhluk terbaik Tuhan, yaitu dimensi kepemilikan. Manusia menurut Gus Dur tidak bisa tidak memiliki sesuatu dalam hidupnya. Itu berarti, memiliki adalah salah satu kodrat manusia yang tak bisa dihilangkan. Bukti mengenai hakikat manusia merupakan makhluk yang berkepimilikan ialah tidak berhasilnya konsep Plato diterapkan di mayarakat. 85 Syamsul Bakri dan Mudhofir, Jombang Kairo, Jombang Chicago: Sintesis Pemikiran Gus Dur dan Cak Nur dalam Pembaruan Islam di Indonesia (Solo: Tiga Serangkai, 2004), Cet. Ke-1, h. 65. 86 Adelbert Snijders, Manusia dan Kebenaran: Sebuah Filsafat Pengetahuan (Yogyakarta: Galang Press, 2010), Cet. Ke-5, h. 217. 45 Konsep Plato tersebut menyebutkan bahwa manusia tidak diperkenankan memiliki sesuatu secara pribadi, segala sesuatu yang dimiliki sesungguhnya bukan miliknya, tetapi milik seluruh umat manusia.87 Konsep itu sudah pernah dicoba diterapkan di negara polisnya, dan dicoba dihidupkan kembali oleh Karl Marx. Tetapi sampai sekarang konsep itu tidak dapat diterapkan dengan sempurna. Hal itu terjadi karena konsep mengenai ketidak pemilikan manusia adalah bertentangan dengan hakikat manusia itu sendiri dan merupakan konsep berupa pemerkosaan terhadap kodrat manusia. Tampaknya fitrah manusia sebagai makhluk yang memiliki dapat melahirkan semangat kepada manusia agar terus berlomba-lomba untuk memiliki sesuatu. Perlombaan itu kemudian melahirkan kemajuan pada suatu individu, dan kalau setiap individu sudah maju, maka kelompok (masyarakat) yang individu yang terdapat dalam suatu negara akan maju seiring dengan majunya tiap individu tersebut. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa akal merupakan salah satu potensi manusia yang sangat penting. Kinerja dari akal disebut berpikir. Maka sesungguhnya manusia merupakan makhluk yang berpikir. Melalui kinerjanya yang berpikir, akal dapat memberikan pencerahan pada manusia agar dapat membedakan antara kebaikan dengan keburukan, serta antara yang bermanfaat dan membahayakan.88 87 Driyarkara, Karya Lengkap Driyarkara: Esai-Esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsanya (Jakarta: Kompas Gramedia, 2006), h. 116. 88 Ibrahim Amini, Risalah Tasawuf: Kitab Suci para Pesuluk, terj. Ahmad Subandi dan Muhammad Ilyas (Jakarta: Islamic Center Jakarta, 2001), h. 61. 46 Gus Dur menegaskan bahwa manusia merupakan makhluk rasional, yaitu makhluk yang mempunyai kemampuan akal.89 Sebagai makhluk rasional, manusia hendaknya mengambil inisiatif untuk mencari wawasan terjauh dari keharusan berpegang pada kebenaran.90 Wawasan terjauh tersebut bisa saja terus menerus mencari sisi-sisi yang paling tidak masuk akal dari kebenaran yang ingin dicari dan ditemukan. Apa yang terkait dengan kemampuan akal manusia itu sebenarnya sangat terkait dengan metafisika. Hasil dari berpikir itulah yang disebut dengan konsep. Tetapi manusia tidak hanya membutuhkan suatu konsep. Lebih dari itu, manusia membutuhkan realisasi terhadap apa yang telah dirumuskan melalui akalnya. Maka realisasi itulah yang disebut dengan berkreasi. Lebih dalam lagi Gus Dur menjelaskan bahwa kreatif mempunyai arti mengambil inisiatif untuk mencari wawasan terjauh dari keharusan berpegang pada kebenaran.91 Manusia boleh mempunyai seribu konsep mengenai hidup yang sejahtera, tetapi ia tidak akan mampu bertahan hidup tanpa berkreasi, atau tanpa merealisasikan apa yang telah disusunnya. Bahwa berkreasi atau berkarya (meminjam istilah Soerjanto Poespowardojo) sebenarnya mempunyai arti yang positif, yakni mempunyai makna 89 yang sangat manusiawi, karena Abdurrahman, Islam Kosmopolitan, h. 30. Abdurrahman, Islam Kosmopolitan, h. 11. 91 Ibid. 90 berkreasi merupakan proses 47 penyempurnaan manusia itu sendiri.92 Dengan demikian dalam kreativitasnya tercermin mutu dan martabat manusia. B. Filsafat Manusia menurut Murtadlâ Muthahharî 1. Perspektif Murtadlâ Muthahharî tentang Manusia Murtadlâ Muthahharî memberikan perhatian yang cukup serius mengenai tema tentang hakikat manusia. Ia banyak membahas hakikat manusia di berbagai buku yang ditulisnya. Bahkan ia menulis buku khusus yang menyoroti tentang manusia, yaitu buku yang berjudul Insone Komel yang dialih bahasakan oleh ʻAbdillâh Ḥâmid Baʻabud menjadi Manusia Seutuhnya: Studi Kritis berbagai Pandangan Filosofis. Penjelasan Muthahharî menganai hakikat manusia sangatlah menarik. Konsep yang ia tawarkan sangat berbeda dengan konsep manusia hakiki sebagaimana banyak orang pahami dari pelopor konsep insân kâmil, Ibn Arabi, yang memang menjadi icon utama dalam perbincangan tentang hakikat manusia. Bahwa apa yang ia sampaikan mengenai manusia yang benar-benar manusia adalah suatu hal yang baru. Muthahharî memandang manusia sebagai makhluk yang terdiri dari apa yang ada pada malaikat dan apa yang ada di hewan.93 Dengan demikian, dalam diri manusia terdapat unsur yang tidak dimiliki malaikat yaitu unsur kehewanan meliputi nafsu, amarah dan lainnya dan juga terdapat unsur yang tidak dimiliki 92 Soerjanto Poespowardojo, “Menuju Manusia Seutuhnya,” dalam Sekitar Manusia (Jakarta: Gramedia, 1983), Cet. Ke-4, h. 5. 93 Murtadlâ Muthahharî, Manusia Seutuhnya: Studi Kritis berbagai Pandangan Filosofis, terj. ʻAbdillâh Ḥâmid Baʻabud (Jakarta: Sadra Institute, 2012), Cet. Ke-1, h. 27. 48 hewan seperti akal dan lainnya. Jika melihat unsur-unsur tersebut, sesungguhnya manusia memang diciptakan untuk diuji, karena unsur-unsur tersebut yang mendorong lahirnya serangkaian potensi. Hal itulah yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang unik dan mempunyai keunggulan melebihi makhluk lain. Manusia merupakan makhluk yang diilhami kebaikan dan keburukan kedalam jiwanya.94 Sehingga dengan itu manusia mampu memahami kebaikan dan keburukan. Karena kebaikan dan keburukan memang sudah tertanam dalam diri manusia, maka meskipun tanpa belajar atau tanpa guru manusia sebenarnya sudah mampu membedakan antara kebaikan dan keburukan. Selain itu ia memposisikan manusia sebagai makhluk yang dalam dirinya terdapat segumpalan potensi-potensi yang memang khas. Karena potensi-potensi tersebut adalah suatu hal yang khas, maka makhluk selainnya tidak mempunyai potensi-potensi sebagaimana manusia miliki. Di sinilah nilai lebih manusia dibandingkan dengan makhluk lain, yaitu memiliki potensi yang tidak dimiliki makhluk lain.. Peneliti handal dari UIN Syarif Hidayatullah, Syamsuri, mengatakan dalam laporan hasil penelitiannya mengenai konsep hakikat manusia Muthahharî, bahwa manusia mempunyai banyak potensi. Potensi itu biasa disebut juga dengan dimensi kemanusiaan atau nilai kemanusiaan. Menurutnya, Muthahharî mengklasifikasikan dimensi-dimensi tersebut setidaknya menjadi 94 Murtadlâ Muthahharî, Islam dan Tantangan Zaman: Rasionalitas Islam dalam Dialog Teks yang Pasti dan Konteks yang Berubah, terj. Ahmad Sobandi (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2011), Cet. Ke-1, h. 321. 49 lima bagian, yaitu dimensi intelektual, dimensi moral, dimensi estetis, dimensi ibadat (ritus) dan dimensi kreativitas.95 Dalam pandangannya mengenai hakikat manusia, ia menjadikan dimensi kemanusiaan tersebut sebagai ukuran yang sangat menentukan kemanusiaan manusia. Manusia yang benar-benar manusia adalah ia yang segala dimensi kemanusiaannya berkembang secara seimbang dan stabil.96 Seimbang dalam hal ini menurutnya ialah seiring perkembangan potensipotensi kemanusiaannya, tercipta juga keseimbangan dalam perkembangannya. Sehingga tak satu pun dari nilai-nilai itu yang berkembang tidak selaras dengan nilai-nilai lain. Manusia seperti itulah yang disebut sebagai imam. Kalau berbicara mengenai perkembangan, tentunya terdapat titik awal dari perkembangan tersebut. Bahwa suatu perkembangan pasti diawali oleh titik rendah dan kemudian bergerak menuju arah yang lebih sempurna. Sama halnya dengan perkembangan manusia menjadi manusia. Titik awal dari kemanusiaan tidak lain ialah berpangkal pada aspek kehewanannya yang kemudian terus berkembang menjadi kemanusiaan.97 Pada mulanya, manusia hanyalah sekadar susunan fisik, tetapi bersamaan dengan perkembangan esensinya, ia menjadi lebih bersifat spiritual. Menurutnya, roh manusia berasal dari keberadaan fisiknya dan berkembang menuju kebebasan. Itu berarti, kehewanannya bertindak sebagai suatu sarang. Di dalam sarang tersebut kemanusiaannya tumbuh dan menjadi sempurna. 95 Syamsuri, “Manusia Sempurna Perspektif Murtadlâ Muthahharî”, h. 36. Murtadlâ, Manusia Seutuhnya, h. 28. 97 Murtadlâ, Perspektif al-Qur’an tentang Manusia dan Agama, h. 68. 96 50 Sehingga kebebasan dinilai olehnya sebagai kemampuan manusia dalam penguasaan terhadap aspek-aspek lainnya. Dengan demikian manusia yang hakiki adalah ia yang menguasai secara relatif, baik lingkungan internal maupun eksternalnya tanpa menghilangkan keimanan dan keilmuan bahkan menguatkan keduanya. Sebagaimana yang diungkapkan dalam bukunya: Individu yang hakiki ialah yang terbebaskan dari ikatan internal maupun eksternal dan mengikatkan diri pada suatu keimanan dan keyakinan.98 Perbedaan yang paling penting dan mendasar antara manusia dan makhluk-makhluk lainya terletak pada iman dan ilmu yang merupakan kriteria kemanusiaannya.99 Maka, kebebasan manusia dari ikatan internal dan eksternal yang kemudian mengikatkan dirinya pada suatu keimanan dan keilmuan merupakan tanda atau ukuran mengenai hakikat manusia. Bahwa, seseorang yang dikatakan perkembangan seluruh nilai kemanusiaannya seimbang dan stabil jika individu tersebut bebas dari segala ikatan internal dan eksternal yang kemudian memupuk keimanan dan keilmuan. Keimanan merupakan media dalam memperluas manusia secara vertikal, sedangkan keilmuan memperluas manusia secara horizontal. Keimanan dan keilmuan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia. Karena keimananlah yang mengilhami manusia tentang apa yang mesti kita kerjakan. Sedangkan keilmuan menunjukkan kepada kita apa yang ada di sana. 98 99 Ibid, h. 68. Ibid, h. 65. 51 Dari apa yang disampaikan di atas, Murtadlâ ingin menekankan bahwa keseimbangan dari segala aspek nilai-nilai kemanusiaan tersebut ditandai oleh keimanan dan keilmuan seseorang. Jika keimanan dan keilmuan seseorang stabil, sudah merupakan kepastian bahwa nilai-nilai kemanusiaannya sudah seimbang sebaigamana dijelaskannya. Karena menurut Murtadlâ, keilmuan saja tidak mampu menyelamatkan manusia dari kehancuran.100 Dengan demikian, puncak hakikat manusia ialah berada pada keimanan dan keilmuannya. 2. Dimensi-Dimensi Manusia Sebagaimana dituliskan dalam buku Muthahharî yang berjudul Bedah Tuntas Fitrah yang diterjemahkan oleh Afif Muhammad, bahwa dimensidimensi manusia tersebut di antaranya ialah mencari kebenaran, moral, estetika, kreasi dan penciptaan, kerinduan dan ibadah. Sedangkan Syamsuri menyebutnya dengan istilah dimensi intelektual, dimensi moral, dimensi estetis, dimensi ibadat (ritus) dan dimensi kreativitas.101 Sebagai salah satu dari dimensi kemanusiaan, dimensi intelektual manusia sebenarnya sudah tertanam dalam diri manusia sejak lahir. Dimensi intelektual itu merupakan dimensi yang melahirkan dorongan-dorongan suci untuk mencari kebenaran. Dalam diri manusia terdapat dorongan-dorongan untuk mengetahui dan menalar hakikat sesuatu.102 Artinya, manusia ingin 100 Murtadlâ Muthahharî, Neraca Kebenaran dan Kebatilan, (Bogor: Ebook yang dipublikasikan oleh www.al-shia.org, 2001), h. 45. 101 Syamsuri, “Manusia Sempurna Perspektif Murtadlâ Muthahharî,” h. 38-43. 102 Murtadlâ Muthahharî, Bedah Tuntas Fitrah: Mengenal Hakikat dan Potensi Kita, terj. Afif Muhammad (Jakarta: Citra, 2011), h. 49. 52 memperoleh pengetahuan-pengetahuan tentang alam dan wujud benda-benda dalam keadaan yang sesungguhnya. Murtadlâ menyebut keadaan itu dengan “kesadaran filosofis” atau “pencarian kebenaran”. Dalam kajian Sidi Gazalba, otak diposisikan sebagai organ yang tak akan berfungsi tanpa adanya jiwa.103 Jiwalah yang kemudian dapat menggerakkan otak, sehingga ia dapat berpikir. Fungsi berpikir ini yang kemudian membedakan dengan hewan. Hewan juga mempunyai otak tetapi tidak dapat berpikir sebagaimana manusia, karena memang hewan tidak memiliki jiwa yang mendorong otak untuk berpikir. Maka keunikan manusia sebagai makhluk berpikir ini yang Murtadlâ sebut dengan dimensi intelektual. Selain itu, manusia akan selalu terarah pada kecenderungankecenderungan moral, yaitu kecenderungan tentang bagaimana ia bersikap.104 Sebagian manusia cenderung pada yang memberikan manfaat secara fisik, selebihnya cenderung pada keutamaan dan kebajikan.105 Kecenderungan pertama ia sebut sebagai kebaikan materi, sedangkan kedua ia sebut sebagai kebaikan spiritual. Dalam diri manusia sebenarnya yang pertama muncul adalah rangsangan kebaikan, bukan kenikmatan.106 Manusia sesungguhnya mempunyai ketergantungan terhadap kebaikankebaikan spiritual. Manusia sangat menyukai kejujuran dan sebaliknya dengan kebohongan. Ketergantungan manusia terhadap kebaikan-kebaikan spiritual 103 Sidi Gazalba, Ilmu, Filsafat dan Islam tentang Manusia dan Agama (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), Cet. Ke-3, h.12. 104 Mujtaba Misbah, Daur Ulang Jiwa, terj. Jayadi (Jakarta: al-Huda, 2008), Cet. Ke-1, h. 16. 105 Murtadlâ, Bedah Tuntas Fitrah, h. 53. 106 Murtadlâ, Perspektif al-Qur’an tentang Manusia dan Agama, h. 95. 53 atau keutamaan itu dibagi menjadi ketergantungan individu dan ketergantungan sosial.107 Ketergantungan individu merupakan ketergantungan terhadap kebaikan yang memang terdapat dalam diri seperti ketergantungan kepada penguasaan diri dan keberanian yang berarti kekuatan hati. Sedangkan ketergantungan sosial ketergantungan terhadap hubungan dengan manusia lainnya. Misalkan senang membantu, bekerjasama, kerja sosial, berbuat baik dan berkorban untuk orang lain, baik dengan jiwa maupun harta. Bahkan, ketergantungan kebaikan spiritual ini merupakan prilaku yang dapat meningkatkan derajat manusia.108 Aspek sosial merupakan bagian terpenting dari ranah moral. Dalam tulisannya ia juga menjelaskan bahwa kepentingan sosial jauh lebih penting di bandingkan kepentingan pribadi, karena terdapat kebahagiaan tersendiri ketika seseorang dapat bersosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, kepantingan umum mesti lebih diutamakan di atas kepentingan perorangan atau bahkan di atas kepentingan pribadi. Karena, jika setiap orang hanya mengutamakan kepentingan pribadi atau perorangan saja, niscaya kepentingan umum, bahkan termasuk kepentingannya sendiri akan terabaikan, karena itu ada sebagian orang yang berkorban demi membela kepentingan umum.109 Dalam wacana Muthahharî mengenai dimensi moral manusia, tampak melandaskan moral tersebut kepada aspek spiritual. Bahwa manusia sesungguhnya akan mencapai kebahagiaan, yang emang diidamkan dalam 107 108 Ibid, h. 53. Jalaluddin Rakhmat, Dahulukan Akhlak di Atas Fiqih (Bandung: Mizan, 2007), Cet. Ke-1, h. 150. 109 Murtadlâ Muthahharî, Dasar-dasar Epistemologi Pendidikan Islam, terj. Muhammad Bahruddin (Jakarta: Sadra, 2011), Cet. Ke-1, h. 251. 54 hidupnya, jika ia seseorang melandaskan hidupnya pada aspek kebaikan spiritual. Hal ini sejalan dengan ungkapan W. Poespoprodjo bahwa moral tersebut harus berlandaskan spiritual, tanpanya moral tidak akan terialisasi dengan baik bahkan gagal.110 Ketertarikan manusia pada kebahagiaan tidak dapat dipungkiri, tetapi ketertarikannya terhadap keindahan pun tidak dapat diabaikan dari kehidupan manusia. Justru karena keindahan-keindahan manusia mampu hidup penuh optimis. Dalam kehidupan sehari-hari misalnya, seseorang tidak akan dapat mengabaikan keindahan pribadi ataupun di luar dirinya. Bagaimanapun juga, manusia akan terus memburu keindahan tersebut. Arahnya yang tak dapat dipisahkan dari keindahan itulah yang disebut dengan dimensi estetis. Itulah keunikan manusia. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang dapat menangkap dunia sekitarnya sebagai suatu yang sangat mengagumkan.111 Artinya manusia mampu menangkap keindahan yang tertuang di balik benda itu sendiri sehingga benda atau alam sekitar itu menjadi mengagumkan. Suatu bentuk (keindahan) yang tidak dapat ditangkap makhluk lain. Dimensi-dimensi kemanusian mempunyai hubungan langsung dengan fitrah dan fitrah dapat ditafsirkan. Penafsirannya ialah dalam diri manusia terdapat hakikat kemanusiaan yang suci. Salah satu di antaranya adalah kecendungan mencari Tuhan. Kecenderungan mencari Tuhan sebenarnya 110 W. Poespoprodjo, Filsafat Moral: Kesusilaan dalam Teori dan Praktek (Bandung: Pustaka Grafika, 1999), Cet. Ke-1, h. 28. 111 Soerjanto Poespowardojo, “Menuju Manusia Seutuhnya,” h. 5. 55 berasal dari kerinduan yang tertanam dalam diri manusia karena kerinduan hakiki manusia menyatu dengan roh manusia, setelah roh itu sampai dan menemukannya. Maka kerinduan itu sendiri berperan sebagai penggerak. Kerinduan tidak ada kaitannya sama sekali dengan kebersamaan dan pertemuan. Ia berpusat dalam diri individu itu sendiri. Kerinduan dapat mengantarkan seseorang pada suatu tingkat yang di situ ia ingin menjadikan yang dicintainya sebagai tuhan (sesuatu yang dipuja) dan dirinya sebagai hambanya. Sehingga yang dicintai disebut sebagai yang mutlak ada dan dirinya sebagai tidak ada. Maka kerinduan itu sendiri yang Murtadlâ sebut sebagai ritus atau ibadat.112 Menurut Murtadlâ Muthahharî, kerinduan yang sangat tinggi ialah kerinduan akan Tuhannya. Kerinduan terhadap Tuhan merupakan suatu kecenderungan manusia untuk dekat dengan Tuhan.113 Dalam artian, manusia sadar akan kehadiran Tuhan jauh di dasar sanubari mereka. Tetapi pertanyaannya ialah kalau memang hakikat manusia itu mempunyai kecenderungan untuk dekat dengan Tuhan, mengapa tidak sedikit orang yang jauh dari-Nya. Muthahharî menjelaskan bahwa lahirnya segala keraguan dan keingkaran manusia kepada Tuhan muncul ketika manusia menyimpang dari fitrah mereka sendiri.114 Terlepas dari kecenderungan manusia untuk mensucikan sesuatu sebagaimana telah diterangkan, manusia masih mempunyai nilai dasar yang 112 Murtadlâ, Bedah Tuntas Fitrah, h. 55. Murtadlâ, Perspektif al-Qur’an tentang Manusia dan Agama, h. 118. 114 Ibid, h. 118. 113 56 tampaknya hal ini sering diabaikan. Bahwa manusia mempunyai ketertarikanketertarikan yang mendasar untuk membuat sesuatu yang belum ada dan belum dibuat orang.115 Membuat sesuatu yang belum ada atau kata lain menciptakan merupakan bentuk dimensi kreativitas manusia. Dalam diri manusia, akan lahir kebahagiaan tersendiri yang menyelimuti hidup seseorang ketika ia mampu berkreasi. Dalam artian, ia mampu berkreasi dan kemudian mengaktualisasikan dalam bentuk nyata. Saat itulah menurut Muthahharî seseorang merasakan kepribadiannya. Merasakan kepribadiannya lewat kreativitas merupakan salah satu tanda bahwa ia benarbenar sadar akan dirinya. Pada saat itu manusia paham bahwa dirinya mampu menciptakan sesuatu dan mampu mewujudkan sesuatu yang bersifat metafisikan menjadi fisika. 115 Murtadlâ, Bedah Tuntas Fitrah, h. 54. BAB IV KOMPARASI PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID DAN MURTADLÂ MUTHAHHARÎ TENTANG FILSAFAT MANUSIA A. Pandangan mengenai Ayat-Ayat tentang Manusia Pandangan Gus Dur dan Murtadlâ Muthahharî mengenai manusia memang tidak akan lepas dari dasar utama agama yang mereka anut, al-Qur’an. Keduanya menjadikan al-Qur’an sebagai landasan utama dalam merumuskan pemikiran mengenai manusia. Tetapi memang mereka menginterpretasikannya dengan cara yang berbeda. Dalam pembahasan mengenai status manusia di muka bumi, keduanya menafsirkan surat al-Baqarah yang menjelaskan tentang ke-khalîfah-an manusia dengan ragam penafsiran yang tidak sama. Misalkan dalam menafsirkan surat al Baqarah/2: 29, berikut teksnya: “Ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalȋfah di bumi. Mereka berkata: mengapa Engkau hendak menjadikan (khalîfah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan dara. Tuhan berfirman: sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” Kata khalȋfah merupakan fȋʻil yang berarti yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya. Tetapi dalam memahami istilah ini, 57 58 khalȋfah diartikan yang menggantikan Allah dalam menegakkan kehendak-Nya dan menerapkan ketetapan-ketetapannya.114 Menurut Gus Dur, posisi manusia sebagai khalîfatullâh merupakan kedudukan tertinggi setelah Tuhan dan lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk lain. Dengan demikian manusia sesungguhnya adalah makhluk kepercayaan Tuhan untuk menggantikan-Nya di muka bumi. Tentunya manusia diberikan kepercayaan sebesar itu dikarenakan ia mempunyai potensi-potensi yang memungkinkannya dapat memahami dan merealisasikan maksud-maksud Tuhan. Kedudukan manusia sebagai khalîfatullâh, Gus Dur maknai sebagai fungsi kemasyarakatan. Dengan itu, manusia mempunyai keharusan untuk memperjuangkan dan melestarikan cita-cita hidup kemasyarakatan yang mampu menyejahterakan manusia itu sendiri secara menyeluruh. Selanjutnya, Islam memberikan hak kepada manusia untuk menjadikan pengganti Allah di muka bumi, sebuah fungsi kemasyarakatan yang mengharuskan kaum muslimin untuk senantiasa memperjuangkan dan melestarikan cita hidup kemasayarakatan yang mampu menyejahterakan manusia itu sendiri secara menyeluruh.115 Ungkapan ini memberikan gambaran kepada penulis bahwa inti dari status manusia sebagai makhluk nomor satu di jagat raya adalah tidak lain kecuali sebagai rahmat atau kesejahteraan bagi seluruh alam. Syaiful Arif116 mengatakan bahwa dalam hal ini Gus Dur memaknai rahmat tidak hanya sebagai kasih sayang, tetapi juga kesejahteraan. Dalam makna kesejahteraan ini, rahmat memiliki makna 114 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, V. I (Jakarta: Lentera Hati, 2007), Cet. Ke-5, h. 142. 115 Abdurrahman Wahid, Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan (Jakarta: The Wahid Institute, 2007) Cet. Ke-1, h. 30. 116 Pengamat pemikiran Gus Dur lulusan Sekolah Tinggi Filsafat (STF) sekaligus tutor kuliah pemikiran Gus Dur di The Wahid Institute. 59 praksis, sebab ia akan mengupayakan kesejahteraan di tengah realitas hidup yang tidak sejahtera.117 Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Gus Dur menginterpretasikannya dengan menggunakan pendekatan sosial. Artinya, manusia sebagai khalîfatullâh diukur dengan peranannya dalam ranah sosial, karena menurut Gus Dur pesanpesan Islam untuk umatnya tidak lain kecuali untuk memberikan kontribusi besar terhadap tatanan sosial yang lebih baik berupa kesejahteraan.118 Pernyataan Gus Dur tentang al-Qur’an sebagai kitab moral119 merupakan upayanya dalam merangsang pembaca yang beriman untuk kembali mengaji alQur’an dengan lebih manusiawi. Tampaknya Gus Dur ingin menunjukkan bahwa tuntunan dalam al-Qur’an tidak mengajarkan umat Islam tentang kekerasan, tetapi mengajarkan tentang pentingnya kedamaian dan kesejahteraan. Maka ini adalah jurus handal Gus Dur untuk memupuskan seluruh bentuk diskriminasi dan penindasan dalam bentuk apa pun. Sedangkan menurut Murtadlâ manusia adalah makhluk pilihan Tuhan yang disebut dengan istilah khalîfatullâh. Manusia diciptakan khusus untuk diuji oleh Allah demi mengukuhkan statusnya sebagai khalȋfah. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan Allah dalam surat al-Anʻam/6: 165, yaitu “Wa huwa al-ladzî jaʻalakum khalâifa al-ardl wa rafaʻa baʻdlukum fauqa baʻdlin liyabluwakum fî mâ âtâkum” (“dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, untuk mengujimu 117 Syaiful Arif, Humanisme Gus Dur: Pergumulan Islam dan Kemanusiaan (Jakarta: The Wahid Institute, 2013), h. 169. 118 Abdurrahman, Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan, h. 153. 119 Abdurrahman Wahid, Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama, Masyarakat, Negara dan Demokrasi (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), Cet. Ke-1, h. xix. 60 tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu”). Sehingga ia mempunyai banyak keunggulan dibandingkan dengan makhluk lain. Keunggulan-keunggulan tersebut merupakan suatu tanda ke-khalȋfah-an manusia itu sendiri. Manusia mempunyai dua dimensi, yaitu makhluk semi-samawi dan semiduniawi. Kedua dimensi tersebut merupakan keunggulan manusia yang tidak dimiliki makhluk lain. Tetapi keunggulan itu bukanlah kriteria manusia sebagai wakil Tuhan. Justru yang menjadikannya sebagai wakil Tuhan yang sesungguhnya ialah tertanamnya keyakinan yang benar dalam dirinya. Dengan demikian, jelaslah bahwa makluk Allah, yang dipujikan oleh para malaikat dan yang berlimpahan dengan segala sesuatu serta kesempurnaan adalah manusia yang berkeyakinan, bukan manusia tanpa keyakinan.120 Jadi, keseimbangan seluruh dimensi kemanusia sesorang ditandai oleh kebenaran keyakinan manusia itu sendiri. Keyakinan mempunyai peranan penting dalam hidup manusia untuk membentuk dirinya munuju pada kesempurnaankesempurnaan yang kemudian mengarahkannya pada penerapan di setiap tindakan. Tentunya tindakan-tindakan yang dimaksud adalah prilaku yang telah tertuang dalam al-Qur’an.121 Dengan demikian, penafsiran yang digunakn Murtadlâ dalam kajian di atas ialah menggunakan pendekatan tauhid. ke-khalȋfah-an manusia menurutnya, tampil ketika ia nilai-nilai tauhid tertanam dengan baik dalam dirinya. Alasannya, tauhid 120 Murtadlâ Muthahharî, Perspektif al-Qur’an tetanng Manusia dan Agama, terj. Haidar Baqir (Bandung: Mizan, 1992), Cet. Ke-6, h. 123. 121 Ibid, h. 123. 61 merupakan langkah dasar menuju kealiman, amal saleh, dan bekerja keras di jalan Allah.122 B. Pandangan tentang Manusia secara Utuh 1. Manusia yang Hakiki Mengenai pandangan kedua tokoh tentang hakikat manusia, masingmasing mempunyai konsep yang menarik. Manusia oleh Gus Dur dipandang sebagai makhluk Tuhan yang sangat mulia. Kemuliaan itu tercermin pada potensi-potensi yang tidak terdapat di makhluk selainnya. Sedangkan Murtadlâ mengatakan bahwa manusia sebenarnya satu-satunya makhluk Tuhan yang diciptakan untuk diuji. Sehingga wajar jika ia dibekali oleh Tuhan kemampuankemampuan yang tidak dimiliki makhluk lain yang tidak diciptakan untuk diuji. Tetapi dalam menjelaskan lebih lanjut mengenai manusia, Gus Dur menitik tekankan hakikat manusia itu kepada penggunaan segala daya upaya manusia untuk kesejahteraan manusia. Daya upaya di sini lebih pada potensi kemanusiaan manusia yang digunakan maksimal dan seimbang demi kemaslahatan bersama. Itu berarti segala usaha manusia dalam segala aktivitasnya hanya untuk kesejahteraan manusia.123 Jadi, manusia itu akan tampil ketika ia benar-benar manusia jika ia kemudian memperjuangkan kesejahteraan umat. Apa yang diungkapkan Gus Dur itu sangat menarik, karena dalam memandang manusia yang juga sama-sama berlandaskan al-Qur’an, tetapi 122 123 Ibid, h. 123. Syaiful, Humanisme Gus Dur, h. 12. 62 melahirkan teori yang berbeda dengan teori Muthahharî mengenai hakikat manusia. Kalau dilihat dari aspek epistemologi, konsep mengenai hakikat manusia Gus Dur dan Murtadlâ sama-sama berlandaskan al-Qur’an dan Hadis. Itu artinya, bahwa konsep kedua tokoh tersebut bersumber dari al-Qur’an dan Hadis. Karena memang, al-Qur’an dan hadis merupakan bagian dari sumber ilmu pengetahuan.124 Karena bersumber dari al-Qur’an dan Hadis, maka pemikiran keduanya tentang manusia pun tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai landasan tersebut. Memang keduanya sama-sama berlandaskan al-Qur’an dalam menyusun konsep hakikat manusia itu sendiri. Tetapi Gus Dur dalam menginterpretasikannya lebih menekankan pada aspek sosial. Baginya, manusia yang sesungguhnya akan tampak ketika segala potensi kemanusiaannya digunakan dan mempunyai dampak sosial yang positif bagi umat manusia. Itulah yang disebut dengan raḥmatan lil ʻâlamîn. Maka seandainya terdapat dua diskriminasi, yaitu diskriminasi terhadap Tuhan dan manusia. Maka manusia seharusnya memilih membela manusia untuk dibebaskan dari diskriminasi itu. Karena Tuhan itu sendiri tidak perlu dibela. Tuhan itu Mahakuasa, jika manusia memilih membela Tuhan, itu sama saja dengan menyepelekan kemahakuasaan Tuhan. Bahkan meletakkan 124 Dinar Dewi Kania, “Objek Ilmu dan Sumber-Sumber Ilmu,” dalam Filsafat Ilmu: Perspektif Barat dan Islam, Adian Husaini et al (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 93-101. 63 kemahakuasaan Tuhan di bawah kekuasaan manusia, karena Ia butuh pertolongan manusia. Gus Dur menjadikan Manusia yang raḥmatan lil ʻâlamîn itu sebagai model manusia paling ideal. Karena itulah hakikat diturunkannya manusia di muka bumi. Manusia diturunkan ke muka bumi untuk mengolah dengan baik baik isi alam demi rahmat untuk seluruh alam termasuk kesejahteraan manusia. Nabi Muhammad lahir di bumi pada hakikatnya diutus untuk membebaskan manusia dari segala penindasan, diskriminasi dan lain sebagainya. Maka hakikat kedatangan Muhammad ialah untuk memanusiakan manusia. Tetapi Muthahharî berpandangan berbeda dengan apa yang disampaikan Gus Dur. Muthahharî menekankan esensi kemanusiaan manusia berada pada aspek ketauhidan. Bahwa manusia yang esensial ialah dia yang beriman. Keimanan menurutnya merupakan hal yang dapat mengarahkan manusia pada cara-cara yang harus ia lalui. Maka yang menjadikan manusia manusia yang utuh itu tampil pada keimanannya.125 Tetapi diredaksi lain ia juga menambahkan bahwa kehakikian manusia tampil juga pada keilmuannya.126 Seseorang yang beriman, dalam tiap tindakannya tentu tidak akan pernah lepas dari ajaran-ajaran Tuhan, yaitu yang tertuang dalam al-Qur’an. Bahwa tindakan manusia yang menjadikannya sebagai manusia yang bertingkah laku sebagaimana dalam al-Qur’an ialah beramal baik, yaitu menggunakan segala 125 126 Murtadlâ, Perspektif al-Qur’an tetanng Manusia dan Agama, h. 123. Ibid, h. 68. 64 potensinya untuk kebaikan dan demi ridha Allah.127 Tentu keimanan yang dimaksud harus dilandaskan pada ilmu, sehingga objek yang diimani tidak salah sasaran. Sebenarnya Gus Dur tidak mengabaikan tauhid atau ketuhanan dalam mengungkapkan teorinya mengenai manusia. Manusia yang hakiki bukan dia yang asal menciptakan kesejahteraan di muka bumi dan kemudian meniadakan Tuhan. Tetapi justru menciptakan kesejahteraan umat manusia itu merupakan suatu bentuk keimanannya kepada Tuhan. Dalam istilah lain, menciptakan kesejahteraan merupakan bentuk aplikasi yang sesungguhnya dari keimanan kepada Tuhan. Yang menarik dari Gus Dur ialah untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, manusia hendaknya tidak memisahkan antara kepentingan hidupnya dan moralitas yang dianutnya.128 Maka, menciptakan kesejahteraan manusia merupakan salah satu bentuk pendekatan diri kepada Tuhan, atau dalam rangka membentuk keimanan seseorang kepada Tuhan itu sendiri. Sedangkan Murtadlâ justru berkebalikan darinya. Untuk menciptakan kesejahteraan, manusia harus beriman. Sedangkan keberimanan manusia merupakan fitrah yang terdapat dalam diri manusia.129 Kalau mengambil contoh cara Nabi Ibrahim dalam membangkitkan keimanannya, ia justru mendapatkan keimanannya melalui pendayagunaan intelegensia secara optimal dan benar. 127 128 Ibid, h. 65. Abdurrahman Wahid, Tuhan tidak Perlu Dibela (Yogyakarta: LKIS, 2010), Cet. Ke-4, h. 85. 129 Murtadlâ Muthahharî, Bedah Tuntas Fitrah: Mengenal Hakikat dan Potensi Kita, terj. Afif Muhammad (Jakarta: Citra, 2011), 135. 65 Maka intelegensia inilah bentuk keilmuan seseorang yang menurut Murtadlâ tidak dapat dipisahkan dari keimanan pada manusia hakiki.130 Maka Muthahharî sesungguhnya lebih menekankan pada ketauhidannya. Kalau manusia sudah beriman, sudah seharusnya ia berprilaku baik kepada seluruh alam demi ridha-Nya. Jadi keimanan bagi Murtadlâ merupakan segalagalanya bagi manusia itu sendiri. Karena imanlah yang menunjukkan bahwa segala potensi kemanusiaannya berjalan dengan maksimal dan seimbang. Sedangkan menurut Gus Dur, segala potensi kemanusiaan manusia tersebut berjalan dengan baik dan seimbang jika manusia mampu memperjuangkan kesejahteraan umat manusia. Tetapi hal yang tidak dapat dipungkiri ialah persamaan anjuran kedua tokoh agar terus berprilaku baik antar sesama dan berlaku arif terhadap lingkungan lingkungan demi kebaikan mamanusia itu sendiri. Di samping itu keduanya juga sama-sama tidak kemudian membuang unsur keyakinan dalam diri manusia dalam melihat manusia yang hakiki tersebut. 2. Dimensi-dimensi Manusia Mengenai dimensi-dimensi manusia yang ditawarkan kedua tokoh tersebut, penulis akan mengalisisnya dengan baik. Gus Dur tidak serta-merta menentukan dimensi-dimensi kemanusiaan. Demikian juga dengan Muthahharî. Keduanya mempunyai landasan-landasan yang cukup menarik menganai dimensi-dimensi manusia itu sendiri. 130 Mulyadi Kartanegara, Renungan-Renungan Filosofis Murtadlâ Muthahharî (Makalah Seminar Internasional Pemikiran Murtadlâ Muthahharî di Auditorium Adhiyana Wisma Antara lt.2, 2004), h. 2. 66 Dalam hal ini, Gus Dur memandang bahwa dimensi-dimensi manusia merupakan aspek terpenting bagi perkembangan manusia menuju kesempurnaannya sebagai makhluk terbaik Tuhan, demikian juga Murtadlâ memandangnya. Hanya saja secara sepintas dimensi-dimensi kemanusia yang ditawarkan kedua tokoh tersebut mempunyai perbedaan-perbedaan istilah. Menurut Gus Dur, dimensi-dimensi manusia yang dimaksud ialah dimensi badani, keyakinan, moral, kepemilikan, kreativitas dan rasionalitas.131 Sedangkan Muthahharî mengistilahkan dimensi-dimensi kemanusiaan itu sebagai dimensi intelektual, moral, estetis, ibadat dan kreativitas.132 Kalau penulis hitung, akan menemukan jumlah klasifikasi yang berbeda antara keduanya. Gus Dur menentukan nilai-nilai dasar tersebut menjadi enam, sedangkan Murtadlâ menentukannya menjadi lima. Tetapi secara substansial, istilah-istilah tersebut mempunyai persamaan-persamaan pembahasan yang mendasar meskipun titik tekannya berbeda. Dari dimensi keyakinan yang diungkapkan Gus Dur tampaknya penulis dapat menelusuru titik temu atau titik persamaan di sela-sela pembahasannya dengan kajian dimensi ibadat menurut Muthahharî. Dimensi keyakinan menurut Gus Dur merupakan dorongan yang lahir dalam diri manusia untuk meyakini keberadaan Tuhan dan menjalankan ajaran-ajaran-Nya.133 Menurut Murtadlâ, dimensi ibadat merupakan kemampuan untuk menjangkau suatu tempat di luar 131 Abdurrahman Wahid, Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan Kebudayaan (Depok: Desantara, 2001), Cet. Ke-2, h. 180. 132 Syamsuri, “Manusia Sempurna Perspektif Murtadlâ Muthahharî” (Laporan Penelitian Dosen Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2001), h. 36. 133 Abdurrahman Wahid, Islam Kosmopolitan, h. 6. 67 alam material dan hasrat untuk menguasai cakrawala yang lebih tinggi dan luas. Hasrat semacam itu merupakan ciri seluruh umat manusia.134 Kajian antara keyakinan dan ibadat merupakan kajian mendasar keagamaan. Dengan demikian, pemikiran kedua tokoh tersebut dipertemukan dalam lingkup keagamaan, bahwa fitrah manusia merupakan dorongannya untuk menjadi makhluk beragama. Hal ini telah disinggung dengan baik oleh Syamsuri dalam penelitiannya, bahwasanya dalam lubuk hati manusia telah tertanam suatu kesadaran untuk beriman dan menyembah Allah (beragama). Dalam kaitannya dengan dimensi moral menurut Gus Dur dan dimensi etis menurut Murtadlâ, penulis dapat menelusuri persamaan pandangan keduanya tentang kedua hal tersebut. Bahwa manusia tidak akan pernah mampu hidup dengan baik dan tidak akan hidup dalam suatu masyarakat tanpa dilandaskan pada nilai-nilai moral. Gus Dur juga membahas pentingnya moralitas itu yang dibingkai dengan istilah etika sosial. Bahkan Gus Dur menyebutkan bahwa al-Qur’an merupakan kitab moral.135 Untuk menjadikannya dekat dengan Tuhan, manusia tidak boleh memisahkan diri antara kepentingan hidupnya dari moralitas yang dianutnya.136 Sedangkan Murtadlâ sendiri juga membahas aspek moralitas manusia tidak pernah lepas dari ranah sosial manusia.137 Maka ketika pembahasan tentang moral, pada hakikatnya hal 134 Murtadlâ, Perspektif al-Qur’an tetanng Manusia dan Agama, h. 131. Abdurrahman, Islamku, Islam Anda, Islam Kita, h. xix. 136 Abdurrahman Wahid, Tuhan tidak Perlu Dibela, h. 85. 137 Murtadlâ Muthahharî, Dasar-dasar Epistemologi Pendidikan Islam, terj. Muhammad Bahruddin (Jakarta: Sadra, 2011), Cet. Ke-1, h. 251. Lihat juga Murtadlâ Muthahharî, Manusia dan Alam Semesta: Konsep Islam tentang Jagat Raya (Ebook yang dipublikasikan oleh www.al-shia.org), h. 93. 135 68 tersebut membahas ranah sosial. Karena moral membahas mengenai hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya. Manusia juga mempunyai dimensi kreativitas. Dalam hal ini, Gus Dur memandang dimensi kreativitas ini sebagai sisi manusia yang begitu penting untuk melahirkan pengembangan-pengembangan dari yang telah ada menjadi hal baru yang begitu bermanfaat untuk kepentingan hidup manusia itu sendiri.138 Maka di sinilah letak persamaan pembahasan istilah bekerja ala Gus Dur dengan istilah kreativitas ala Murtadlâ. Karena Murtadlâ memaknai kreativitas dengan menciptakan sehingga melahirkan hal baru yang bermanfaat.139 Dimensi rasionalitas manusia dalam pandangan Gus Dur tampaknya tidak berbeda dengan dimensi intelektual menurut Murtadlâ. Murtadlâ menyatakan bahwa dorongan manusia untuk mengetahui dan menalar hakikat sesuatu merupakan dimensi intelektual manusia.140 Bahkan manusia tidak hanya mengetahui, tetapi juga mampu menemukan tentang hukum alam semesta dan kebenaran umum yang berlaku di dunia.141 Sedangkan nalar merupakan aktivitas berpikir manusia yang oleh Gus Dur disebut sebagai fungsi akal. Maka manusia merupakan makhluk yang mempunyai kemampuan akal.142 Mengenai dimensi-dimensi manusia berikutnya, tampaknya kedua tokoh tersebut mengalami perbedaan yang signifikan. Misalkan dimensi materi dan kepemilikan dalam pandangan Gus Dur tidak terdapat dalam segenap susunan 138 Abdurrahman Wahid, Islam Kosmopolitan, h. 11. Murtadlâ, Bedah Tuntas Fitrah, h. 54. 140 Ibid, h. 49. 141 Murtadlâ Muthahharî, Manusia dan Alam Semesta: Konsep Islam tentang Jagat Raya (Bogor: ebook yang dipublikasikan oleh www.al-shia.org), h. 4. 142 Abdurrahman, Islam Kosmopolitan, h. 30. 139 69 nilai-nilai kemanusiaan yang dirangkai Murtadlâ. Sebaliknya, dimensi estetis yang menurut Murtadlâ merupakan bagian dari unsur dasar kemanusian, ternyata Gus Dur tidak menjadikannya sebagai bagian dari unsur-unsur dasar kemanusiaan. Tidak hanya itu, perbedaan yang mencolok dari pemikiran keduanya ialah penekanan dan orientasi penyusunan dimensi-dimensi manusia. Gus menitik tekankan pada dimensi-dimensi universal manusia yang mengarah pada kesejahteraan. Artinya, manusia akan sempurna jika unsur-unsur universal manusia itu digunakan secara optimal dan seimbang demi terlahirnya kesejahteraan umat manusia. Sedangkan Murtadlâ, berorientasi pada keimanan dan keilmuan. 3. Tentang Kebebasan Manusia Perdebatan mengenai kebebasan sudah tidak lagi menjadi kajian yang baru dalam dunia pemikiran. Tetapi tema ini akan tetap menjadi kajian yang menarik karena perdebatan mengenainya tidak pernah tuntas dan menjadi lebih menarik lagi ketika konsep tentang kebebasan tersebut dikontektualkan. Dalam tiap perjalanan hidup manusia, akan terus menghasilkan pengalaman-pengalaman yang berbeda tiap individu. Dua orang yang berkunjung ke Burobudur, salah satunya tidak dapat menyalahkan atau membenarkan pengalaman lainnya, karena apa yang dialami dan dipikirakan tiap individu mengenai Burobudur merupakan suatu yang berbeda. Maka pemaksaan terhadap orang lain untuk menerima kebenaran mutlak pengalaman seseorang 70 sehingga menyalahkan pengalaman lainnya merupakan tindakan tidak rasional.143 Ulasan di atas menampilkan konsep kebebasan manusia dalam berpikir. Bahwa tiap individu mempunyai kesempatan untuk berpikir berbeda dengan orang lain yang tak bisa dapat disalahkan dan dipaksakan oleh orang lain. Dalam konsep kebebasan Gus Dur memperlihatkan pentingnya saling mengerti dan menghormati antara individu yang juga mempunyai kebebasan yang sama. Seseorang yang sudah mencapai taraf ini akan merasa bahagia dan bangga atas perbedaan yang dimilikinya dan tidak kemudian memaksakan pemikirannya kepada orang lain. Maka kebebasan manusia menurut Gus Dur ialah kehendak manusia yang tidak dipaksa oleh segala kehendak di luar dirinya. Dalam artian, kehendaknya adalah keputusan yang dilakukan oleh diri sendiri secara sadar. Tetapi kebebasan itu tidak didasarkan pada egoisme, tetapi lebih tepat harus didasarkan pada jiwa kemanusiaan.144 Menurutnya, manusia adalah makhluk berpikir yang memiliki kebebasan menggunakan rasionya. Bahwa kemerdekaan berpikir manusia harus dijunjung tinggi karena ia adalah keniscayaan dalam Islam.145 Tetapi kemerdekaan itu tidak menjadikan manusia bebas berpikir tanpa batas. Dalam memahami kemerdekaan berpikir ala Gus Dur, kita harus melanjutkannya pada suatu titik mengenai batas-batas kemerdekaan itu. 143 Abdurrahman, Islamku, Islam Anda, Islam Kita, h. 67. Ibid, h. 307. 145 Ibid, h.143. 144 71 Manusia tidak akan pernah mampu berpikir sebegitu bebasnya, karena ia mempunyai banyak kekurangan-kekurangan. Manusia tak dapat berpikir dengan kemerdekaan yang sempurna kerena yang sempurna itu hanyalah Allah. Maka batasan-batas kemerdekaan manusia ialah kesempurnaan Allah. Kebebasan berpikir ini hendaknya harus diimbangi dengan kesadaran akan kebebasan individu, bahwa setiap individu memiliki kebebasan yang sama antara yang satu dan yang lainnya. Tiap individu mempunyai peluang berpendapat yang sama, sehingga tiap individu juga berpeluang yang sama untuk berbeda pendapat mengenai hasil pemikirannya tentang suatu objek. Tetapi perbedaan itu tidak merupakan malapetaka bagi kehidupan manusia, bahkan perbedaan itu adalah rahmat.146 Tetapi dalam berpikir, manusia seharusnya berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan,147 keadilan, menghormati dan bersikap benar terhadap fakta.148 Kebebasan manusia untuk berpikir merupakan senjata utama dalam mencari solusi problematika hidup yang kemudian dilengkapi dan didukung dengan fasilitas-tasilitas lain. Segala fasilitas itu dituangkan Tuhan kepada manusia karena manusia memang disiapkan untuk menentukan nasibnya sendiri. Tuhan hanya menyediakan kehidupan itu sendiri.149 Dalam surat al-Baqarah/2: 61 difirmankan bahwa “wa dluribat ʻalaihimu al-dzillatu wa al-maskanatu wa bâ’û bi ghadlabin mina Allahi” (”dibuatkan 146 Ibid, h. 145. Ibid, h. 307. 148 Ibid, h. 335. 149 Abdurrahman, Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan, h. 102. 147 72 bagi kaum mulimin kehinaan dan kemiskinan”). Menurut Gus Dur, ayat ini menjelaskan bahwa Islam menolak kemiskinan sebagai sesuatu yang langgeng dan tetap. Maka dari itu, manusia mempunyai kebebasan untuk tetap melestarikan kemiskinan tersebut atau merubahnya menjadi kekayaan. 150 Maka Allah tidak menentukan nasib manusia, melainkan manusia sendiri yang menentukan.151 Bahkan dalam menentukan kebenaran, termasuk kebenaran suatu agama, Tuhan menyerahkannya kepada akal sehat manusia.152 Itu berarti pilihan agama bagi seseorang merupakan pilihan akal sehatnya yang merupakan bentuk kebebasannya. Hal ini menunjukkan keharusan kepada manusia untuk menghormati keputusan-keputusan seseorang dalam memilih agamanya. Tetapi dalam tulisannya yang berjudul Kerangka Pengembangan Doktrin Ahlu al-sunnah wa al-Jamaʻah, Gus Dur membatasi kebebasan manusia pada kekuasaan Tuhan yang menurutnya tidak dapat dilawan. Manusia diperkenankan menghendaki apa saja yang dimaunya, walaupun kehendak itu sendiri harus tunduk kepada kenyataan akan kekuasaan Allah yang tidak dapat dilawan lagi.153 Sayangnya, Gus Dur tidak melanjutkan menjelaskan konsep kuasa Tuhan atas manusia itu. Tetapi kalau melihat latar belakang Gus Dur, konsep itu sama dengan teori yang diungkapkan Asy’ariyah. Bahwa manusia mempunyai kemerdekaan kehendak tetapi atas persetujuan Tuhan.154 150 Abdurrahman, Islamku, Islam Anda, Islam Kita, h. 215. Abdurrahman, Tuhan tidak Perlu Dibela, h. 91. 152 Abdurrahman, Islamku, Islam Anda, Islam Kita, h. 14. 153 Abdurrahman, Islam Kosmopolitan, h. 35. 154 Mulyadi Kartanegara, Menyelami Lubuk Tasawuf (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 81. 151 73 Dalam memandang hal ini, Murtadlâ Muthahharî juga berkomentar mengenai kebebasan manusia. Menurutnya, manusia bebas dari kungkungan kekuatan absolut yang menjadikannya tertekan ketakutan. Maka dari itu sesungguhnya takdir Tuhan tidak membatasi kebebasan manusia, melaikan hanya sebagai hakikat sejati.155 Artinya taqdir Tuhan merupakan keputusan mutlak dari peristiwaperistiwa dan fenomena-fenomena. Dalam kata lain, taqdir merupakan ketetapan suatu hukum yang pasti mengenai suatu kejadian seperti hukum kausalitas. Manusia memang bebas dari pengaruh taqdir Tuhan secara langsung mengenai tindakannya dan kehendaknya, tetapi ia tidak akan pernah bebas dari hukumhukum yang telah ditentukan tadi. Tetapi ketetapan itu tidak menjadikan manusia terbelenggu, justru hal tersebut yang mengahruskan manusia agar memiliki kehendak bebas dan sifat yang penuh kearifan. Sedangkan kebebasan itu sendiri ialah tidak adanya berbagai rintangan dalam jalan pertumbuhan.156 Dengan demikian manusia akan mampu sepenuhnya membebaskan diri dari kepatuhan terhadap kendali lingkungan dan sosial, serta mengatur nasib mereka. Sebagaimana ia ungkapkan dalam bukunya. Ketetapan Ilahi itu mengharuskan manusia memiliki kearifan dan kehendak bebas, agar mereka mampu sepenuhnya membebaskan diri dari kepatuhan terhadap kendala lingkungan dan sosial, serta mengatur nasib mereka.157 155 Murtadlâ, Perspektif al-Qur’an tetanng Manusia dan Agama, h. 143. Murtadlâ Muthahharî, Wacana Spiritual, terj. Strio Pinandito (Jakarta: Firdaus, 1991), h. 39. 157 Murtadlâ, Perspektif al-Qur’an tentang Manusia dan Agama, h. 143 156 74 Ungkapan di atas juga memeberikan penulis penjelasan bahwa kebebasan manusia itu tidak hanya dipandang dari kebebasannya dari belenggu kekuatan Tuhan yang absolut itu. Tetapi juga dilihat dari aspek sosial. Bahwa manusia yang bebas adalah manusia yang tidak patuh terhadap lingkungan dan sosial yang kemudian bebas mengatur nasibnya. Kebebasan sosial ialah kebebasan manusia dalam hubungannya dengan individu-individu lain dalam suatu masyarakat sehingga tidak menghalangi pertumbuhannya, tidak memenjarakannya untuk mencegah berbagai aktivitasnya, tidak memeras atau memperbudaknya, tidak memeras segala kekuatan fisik dan mentalnya demi berbagai kepentingannya sendiri, yang dapat pula digolongkan ke dalam beberapa jenis.158 Orang lain tidak boleh menghalangi pertumbuhannya dan tidak mempersiapkan sarana bagi kesempurnaannya dan tidak menggunakan seluruh kemampuan pemikiran dan fisiknya untuk kepentingan mereka. Satu dari tujuan diutusnya para nabi adalah memberikan kebebasan sosial kepada manusia. Yakni, menyelamatkan manusia dari tawanan dan penghambaan kepada orang lain. Tidak hanya itu, Murtadlâ juga menjelaskan tentang kebebasan dari tekanan-tekanan internal seseorang. Dalam artian, manusia adalah makhluk yang bebas dari belenggu diri sendiri.159 Tidak berhenti di situ, ia melanjutkan lagi 158 159 Murtadlâ, Wacana Spiritual, h. 40. Murtadlâ, Perspektif al-Qur’an tetanng Manusia dan Agama, h. 68. 75 dengan kalimat “dan mengikatkan diri pada keimanan dan keyakinan.160 Tampaknya mengikatkan diri pada keimanan dan keyakinan itulah yang disebut dengan kebebasan spiritual. Kebebasan spiritual ialah kebebasan diri seseorang terhadap kebebasan sosial, kebebasan dari berbagai ikatan yang lain.161 Kecenderungan spiritual yang tertuang dalam diri manusia menjadikannya berusaha untuk terus melangkah di jalan pertumbuhan dan kesempurnaan spiritual dan tidak mengikuti kecenderungan materi saja. Itu berarti bebas dari rakus, ketamakan, syahwat, marah dan hawa nafsu dapat merealisasikan kebebasan spiritual. Orang-orang yang bebas secara hakiki di dunia ini adalah mereka yang pada awalnya telah membebaskan dirinya dari tawanan hawa nafsu. Ia mencontohkannya pada pandangan seseorang kepada seorang wanita tetapi ia mencegah dorongan nafsu tersebut dan mematuhi kesadarannya. Orang yang demikian, Murtadlâ menyebutnya sebagai manusia bebas.162 Muthahharî menilai kebebasan spiritual sangat penting dalam kehidupan manusia, bahkan menyebutnya sebagai sarana bagi manusia untuk meraih kebebasan sosial. Dengan kata lain, manusia yang telahmencapaikebebasan spiritual, manusia yang mendapat didikan ajaran para nabi, pasti menghormati hak-hak sosial manusia lainnya. Mereka tidak akan melakukan kezaliman, berbuat yang melampaui batas dan menghianati orang lain. 160 Ibid, h. 68. Murtadlâ, Wacana Spiritual, h. 54. 162 Ibid, h. 61. 161 76 Tampaknya kedua tokoh tersebut sama-sama mengakui kebebasan manusia dalam menentukan pilihan-pilihan hidupnya. Hal tersebut tampak pada paparan di atas tentang kemampuan manusia untuk bebas. Maka menurut keduanya, manusia mampu menjadi orang berilmu atau menjadi orang bodoh sekalipun. Tetapi dalam mencapai pilihan-pilihan itu tetap membutuhkan usahausaha yang mengarah pada pilihan-pilihan tersebut. Tetapi memang kalau menurut Gus Dur, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh kemahabebasan Tuhan. Artinya sebebas-bebasnya manusia, tetap Tuhan yang mengiyakan segala keputusan manusia. Hanya saja, usaha manusia sangat berpengaruh terhadap keputusan Tuhan, meskipun keputusan bebas Tuhan itu sendiri tidak dapat diintervensi. Sedangkan Murtadlâ menyatakan bahwa kebebasan manusia itu dibatasi oleh kepastian hukum alam. Manusia bisa menjadi orang pintar jika ia melalui proses-proses alam yang telah ditentukan Tuhan. Misalkan jika ia mempunyai otak untuk berpikir, dan berusaha untuk mengasah otak untuk menjadi orang pintar. C. Refleksi Pemikiran Abdurrahman Wahid dan Murtadlâ Muthahharî Dari hasil kajian sebelumnya, pemikiran keduanya dapat penulis singkat dalam beberapa paparan dalam tabel di bawah. Tijauan Pandangan terhadap ayat tentang Abdurrahman Wahid Murtadlâ Muthahharî juga mendasarkan Gus Dur melandaskan Murtadlâ konsepnya tentang manusia pada pemikirannya tentang manusia dalam al-Qur’an. Ia al-Qur’an, tetapi ia memaknai teksmemahami ayat-ayat teksnya menggunakan pendekatan 77 manusia menggunakan pendekatan sosial. Misalkan Gus Dur memaknai kata raḥmah (manusia sebagai dengan raḥmah untuk seluruh alam) dengan kesejahteraan. Itu berarti kesempurnaan manusia oleh Gus Dur dilihat dari seberapa banyak ia dapat memberikan manfaat berupa kesejahteraan kepada seluruh umat manusia. Gus Dur membangun konsepnya tentang manusia menitik beratkan pada ranah sosial. Baginya hakikat manusia ialah ia yang mampu merealisaskan inti ajaran Tuhan, yaitu berupa Hakikat mewujudukan kesejahteraan manusia bagi seluruh umat. Kesejahteraan menjadi tujuan luhur di atas apa pun. Maka merealisasikan kesejahteraan merupakan bentuk keberimanannya kepada Tuhan. Gus Dur merumuskan dimensi-dimensi manusia berdasarkan kulliyah alDimensikhamsah yang pernah dimensi diungkapkan al-Ghazâlî. manusia Tetapi terdapat titik temu dalam pembahasan. Yaitu dimensi keyakinan, moral, kreativitas dan rasionalitas Manusia mempunyai kebebasan memilih sehingga Kebebasan dapat merubah nasibnya, manusia meskipun pada akhirnya kebebasan itu dibatasi oleh ketidak terbatasan Tuhan. tauhid. Dalam istilah manusia khalȋfah tampil ketika ia nilai-nilai tauhid tertanam dengan baik dalam dirinya. Alasannya, tauhid merupakan langkah dasar menuju kealiman, amal saleh, dan bekerja keras di jalan Allah. Jelaslah bahwa kesempurnaan manusia itu diukur dari keyakinan seseorang. Murtadlâ menekankan pada aspek teologis. Menurut Murtadlâ manusia yang utuh ialah ia yang menyeimbangkan segala potensinya demi mencapai tujuan tertinggi yaitu berkeyakinan/berkeimanan. Sedangkan keyakinan yang benar ialah keyakinan kepada Allah. Tetapi ia juga mengakui bahwa manusia juga mempunyai tugas untuk berbuat baik untuk ridha-Nya Sedangkan Murtadlâ berdasarkan pada teks ayat tentang dimensi manusia yang membedakannya dengan makhluk lain. Titik temunya ialah pada pembahasan tentang dimensi ibadat, moral, kreativitas dan intelektual. Manusia mempunyai kebebasan memilih dan menentukan nasibnya sesuai dengan hukum-hukum alam yang telah ditentukan Allah. 78 Bagi Gus Dur nilai-nilai dasar kemanusiaan merupakan unsur universal manusia yang harus dikembangkan dengan optimal dan seimbang untuk mencapai hakikat dirinya sebagai rahmat bagi seluruh alam, atau untuk menciptakan kesejahteraan. Salah satu unsur universal itu ialah unsur rohani yang dengannya manusia terdorong secara fitrah untuk berkeyakinan. Sedangkan keyakinan yang paling tinggi ialah keyakinan kepada Tuhan sesuai dengan agama masingmasing.163 Tampaknya Gus Dur memaknai keyakinan secara universal tanpa mengarah pada keyakinan umat Islam (keyakinan kepada Allah). Maka keyakinan kepada Tuhan bermakna kepercayaan tiap pemeluk agama kepada Tuhan sesuai dengan ajaran agamanya. Karena seluruh Tuhan agama pasti akan selalu mengajarkan kebaikan dan memerintah untuk menebarkan rahmat atau kesejahteraan. Dengan demikian, setiap manusia yang berkeyakinan –entah apa pun agamanya- mempunyai kesempatan yang sama untuk mencapai manusia sejati, makhluk tertinggi setelah Tuhan. Dalam Islam, makhluk yang mencapai derajat tertinggi tersebut ialah Nabi Muhammad. Bahkan Gus Dur menjadikan Nabi Muhammad sebagai satu-satunya manusia yang mencapai kesempurnaan paling tinggi di antara umat-umat lain. Tampaknya Gus Dur ingin memperlihatkan bahwa Islam yang ditampilkan Muhammad adalah ajaran terbaik yang patut dijadikan model/landasan utama seluruh umat manusia dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Tampa disadari Gus Dur sebenarnya berkampanye tentang kesempurnaan Islam. 163 Abdurrahman, Islam Kosmopolitan, h. 4. 79 Konsep ini menjadi sangat menarik ketika dihadapkan pada era kontemporer yang menuntut umat manusia selalu ikut arus globalisasi. Alasannya, konsep Gus Dur tentang manusia ingin membetuk manusia yang berkarakter dan beridentitas tanpa menutup diri dari apa pun di luarnya. Tetapi konsep ini hanya bisa dipahami kalangan tertentu seperti akadimisi. Jika disajikan kepada khalayak ramai, konsep ini akan disalah artikan. Jika ini terjadi, yang tercipta bukan malah manusia yang beridentitas, tetapi malah tercipta manusia tanpa identitas. Di sisi lain, pengakuan terhadap kebenaran agama lain sebagai bentuk saling menghormati antarsesama demi kesejahteraan bersama, akan melahirkan kesan bahwa terdapat banyak kebenaran dalam satu individu. Sehingga, satu orang orang awam yang tidak paham dapat menganut enam agama sekaligus. Jika ini terjadi yang lahir bukan kedamaian dan kesejahteraan, justru pertikaian yang akan mewarnai konsep manusia sejahtera itu. Sedangkan bagi Murtadlâ keseimbangan unsur-unsur universal manusia yang melekat dalam diri manusia merupakan aspek terpenting dalam mencapai manusia hakiki. Seseorang akan tampak sebagai manusia hakiki jika ia benar-benar tampil sebagai manusia yang berkeyakinan dan berilmu. Namun, Murtadlâ menggaris bawahi istilah keyakinan yang dibarengi dengan ilmu. Manusia memang makhluk yang berkeyakinan, tetapi keyakinan harus diimbangi dengan ilmu pengetahuan. Karena keyakinan tanpa ilmu akan melahirkan keyakinan terhadap objek yang salah. Sedangkan keyakinan yang benar ialah keyakinan kepada Allah. 80 Tampaknya Murtadlâ ingin mengatakan bahwa yang mempunyai kesempatan untuk mencapai hakikat manusia hanyalah umat yang beriman kepada Allah demikan juga dengan ajarannya. Seseorang yang berkeyakinan, sedangkan keyakinannya tersebut tidak kepada Allah, tentu ia tidak mengoptimalkan potensi intelektualnya dengan baik dan seimbang. Kalau digunakan dengan baik dan seimbang, orang tersebut pasti akan menemukan keyakinan yang benar, yaitu keyakinan kepada Allah. Nah, yang perlu dipertanyakan ialah “Di mana letak universalitas dari ajaran Murtadlâ tentang hakikat manusia jika pada akhirnya yang berhak menjadi manusia sempurna hanyalah manusia yang berkeyakinan/beriman kepada Allah?” Maka konsep Murtadlâ ini tampaknya bersifat eksklusif. BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Gus Dur memandang bahwa manusia merupakan makhluk yang unggul karena mempunyai beberapa dimensi, di antaranya ialah dimensi badani, keyakinan, moralitas, kepemilikan, kreativitas dan rasionalitas. Manusia akan mencapai hakikat dirinya sebagai manusia, jika seluruh dimensi-dimensi tersebut diberikan kebebasan untuk mengekpresikan segala kemampuannya. Dengan demikian dimensi-dimensi tersebut harus dilindungi agar tidak ada benturan antara kebebasan yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut Murtadlâ, manusia adalah makhluk yang diciptakan untuk diuji, karena di dalamnya terdiri dari apa yang terdapat di malaikat dan hewan. Kedua unsur yang mendorong lahirnya serangkaian potensi. Potensipotensi tersebut antara lain ialah kebenaran, moral, estetika, kreasi dan penciptaan, kerinduan dan ibadah. Keseimbangan dari potensi-potensi itu adalah tanda bahwa seseorang tersebut telah berada pada tingkat hakikatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang unggul. Antara Gus Dur dan Murtadlâ sama-sama menjadikan al-Qur’an sebagai landasan utama pemikiran mereka tentang manusia. Sehingga pemikiran keduanya tetap sama-sama tidak akan keluar dari nilai-nilai al-Qur’an. Sehingga keduanya sama-sama ingin membawa manusia pada keadaan yang lebih baik. Tidak hanya itu, pemikiran keduanya juga dipertemukan dalam konsep tentang dimensi-dimensi manusia. Misalkan, dimensi keyakinan yang dikonsep Gus Dur dan dimensi ibadat 81 82 dalam konsep Murtadlâ dipertemukan dalam bingkai agama. Bahwa bahwa tidak akan pernah lepas dari fitrahnya sebagai manusia yang beragama. Beragama yang dimaksud ialah berkeyakinan dan beribadah kepada yang diyakininya. Tetapi dalam menafsirkan al-Qur’an, keduanya menggunakan metode yang berbeda. Gus Dur menafsirkan menggunakan pendekatan sosial, sedangkan Murtadlâ menafsirkan menggunakan pendekatan tauhid. Sehingga hasilnya pun menitik beratkan pada ranah yang berbeda. Gus Dur menitik beratkan pada aspek kesejahteraan, sedangkan Murtadlâ lebih pada aspek keimanan. B. Saran-Saran Kajian ini tentu tidak sempurna, sehingga diperlukan kajian-kajian yang lebih mendalam mengenai tema tersebut, karena kajian ini menyangkut hakikat diutusnya manusia ke muka bumi. Dengan mengetahui tugas dan perannya di muka bumi, ia akan hidup dengan benar, yaitu hidup sesuai dengan keharusankeharusan sebagaimana Yang juga tidak kalah pentingnya ialah mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari segala hasil penelitian ini. Sehingga konsep ini benar-benar bermanfaat. DAFTAR PUSTAKA Amini, Ibrahim. Risalah Tasawuf: Kitab Suci Para Pesuluk, terj. Ahmad Subandi dan Muhammad Ilyas. Jakarta: Islamic Center Jakarta, 2001. Arif, Syaiful. Humanisme Gus Dur: Pergumulan Islam dan Kemanusiaan. Jakarta: The Wahid Institute, 2013. Bagir, Haidar. Membincang Metodologi Ayatullâh Murtadlâ Muthahharî. Yogyakarta: UGM, 2004. ____________. Murtadlâ Muthahharî, Sang Mujahid Sang Mujahid. Bandung: Yayasan Muthahharî, 1998. ____________. Resensi Buku Murtadlâ Muthahharî: Pengantar Epistemologi Islam: Sebuah Pemetaan dan Kritik Epistemologi Islam atas Paradigma Pengetahuan Ilmiah dan Relevansi Pandangan Dunia. Jakarta : Sadra Press, 2010. Bagus, Loren. Kamus Filsafat. Jakarta: Gramedia, 2005. Bahar, Ahmad. Biografi Kiai Politik Abdurrahman Wahid: Gagasan dan Pemikiran. Jakarta: Bina Utama, 1999. Bahruddin. Paradigma Psikologi Islam; Studi tentang Elemen Psikologi dari alQur’an. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004. Bakhtiar, Amtsar. Filsafat Agama: Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia. Jakarta: Grafindo Persada, 2009. Bakri, Syamsul dan Mudhofir. Jombang Kairo, Jombang Chicago: Sintesis Pemikiran Gus Dur dan Cak Nur dalam Pembaruan Islam di Indonesia. Solo: Tiga Serangkai, 2004. Barton, Greg. Bografi Gus Dur, terj. Lia Hua. Yogyakarta: LKiS, 2003. ___________, “Liberalisme: Dasar-dasar Progresivitas Pemikiran Abdurrahman Wahid” dalam Greg Barton dan Greg Fealy (ed), Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara, terj. Ahmad Suaedy dkk. Yogyakarta: LKiS, 1997. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1987. Dewan Ensiklopedi Islam. Ensiklopedi Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997. Dhakiri, M. Hanif. 41 Warisan Kebesaran Gus Dur. Yogjakarta: LKiS, 2010. 83 84 Driyarkara. Karya Lengkap Driyarkara: Esai-esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsanya. Jakarta: Kompas Gramedia, 2006. Efendi, Djohan. “Gus Dur: Sang Presiden yang Humanis,” dalam Ahmad Gaus AF, Sang Pelintas Batas: Biografi Djohan Efendi. Jakarta: ICRP, 2009. Gazalba, Sidi. Ilmu, Filsafat dan Islam Tentang Manusia dan Agama. Jakarta: Bulan Bintang, 1992. Hadrianto, Budi. 50 Tokoh Islam Liberal Indonesia Pengusung Ide Sekulerisme, Pluralisme, dan Liberalisme Agama. Jakarta: Hujjah Press, 2007. Ismail, Faizal. Dilema NU di Tengah Badai Pragmatisme Politik. Jakarta: Mitra Cendikia, 2004. al-Jîlî, Abdul Karîm Ibnu. Insân Kâmîl: Ikhtisar Memahami Kesejatian Manusia dengan Sang Khaliq hingga Akhir Zaman. terj. Misbah el-Majid, Surabaya: Pustaka Hikma Perdana, 2006. Kania, Dinar Dewi. “Objek Ilmu dan Sumber-sumber Ilmu,” dalam Filsafat Ilmu: Perspektif Barat dan Islam, Adian Husaini et al. Jakarta: Gema Insani, 2013. Kartanegara, Mulyadi. Menyelami Lubuk Tasawuf. Jakarta: Erlangga, 2006. _________________. Nalar Religius: Memahami Hakikat Tuhan, Alam dan Manusia. Jakarta: Erlangga, 2009. __________________. Renungan-renungan Filosofis Murtadlâ Muthahharî. Makalah Seminar Internasional Pemikiran Murtadlâ Muthahharî di Auditorium Adhiyana Wisma Antara lt. 2, 2004. Kurniawan, Wawan. “Menolak HAM atau Mengubah Fiqh?: Pemikiran Gus Dur tentang Islam dan HAM,” Kajian Kebudayaan dan Demokrasi, Weltanscauung Gus Dur. Edisi. vi, Juni 2010. Kurzman, Charles. Wacana Islam Liberal; Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Glogal, terj. Bahrul Ulum dan Heri Junaidi. Jakarta: Paramadina, 2003. Labib, Muhsin. Filosof Sebelum dan Sesudah Mulla Shadra. Jakarta: Lentera, 2005. Misbah, Mujtaba. Daur Ulang Jiwa, terj. Jayadi. Jakarta: al-Huda, 2008. 85 Muthahharî, Murtadlâ. Bedah Tuntas Fitrah: Mengenal Hakikat dan Potensi Kita, terj. Afif Muhammad. Jakarta: Citra, 2011. ___________________. Dasar-dasar Epistemologi Pendidikan Islam, terj. Muhammad Bahruddin. Jakarta: Sadra, 2011. ___________________. Islam dan Tantangan Zaman: Rasionalitas Islam dalam Dialog Teks yang Pasti dan Konteks yang Berubah, terj. Ahmad Sobandi. Jakarta: Pustaka Hidayah, 2011. ___________________. Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam. Bandung: Mizan, 2009. ___________________. Manusia dan Alam Semesta: Konsep Islam tentang Jagat Raya. Ebook yang dipublikasikan oleh www.al-shia.org. ___________________. Manusia Seutuhnya: Studi Kritis berbagai Pandangan Filosofis, terj. ʻAbdillâh Ḥâmid Baʻabud. Jakarta: Sadra Institute, 2012. ___________________. Mutiara Wahyu, terj. Syekh Alî al-Ḥamîd. Bogor: Cahaya, 2004. ___________________. Neraca Kebenaran dan Kebatilan. Bogor: Ebook yang dipublikasikan oleh www.al-shia.org, 2001. ___________________. Perspektif al-Qur’an tentang Manusia dan Agama, terj. Haidar Bagir. Bandung: Mizan, 1992. Nasr, Seyyed Hossein. Islam Tradisi di Tengah Kancah Dunia Modern, terj: Luqman Hakim. Bandung: Penerbit Pustaka, 1994. Nicholson, R.A.. Tasawuf Cinta: Studi atas Tiga Sufi; Ibn Abî al-Khair, al-Jîlî dan Ibn al-Farid, terj. Uzair Faizan. Bandung: Mizan, 2003. Poespoprodjo, W.. Filsafat Moral: Kesusilaan dalam Teori dan Praktek. Bandung: Pustaka Grafika, 1999. Poespowardojo, Soerjanto. “Menuju Manusia Seutuhnya,” dalam Sekitar Manusia. Jakarta: Gramedia, 1983. Qamar, Mujamil. NU Liberal dari Tradisionalisme ke Universalisme Islam. Bandung: Mizan, 2002. Rakhmat, Jalaluddin. Dahulukan Akhlak di Atas Fiqih. Bandung: Mizan, 2007. Rapar, Jan Hendrik. Pengantar Filsafat. Yogyakarta: Kanisius, 2010. 86 Santoso, Listiyono. Teologi Politik Gus Dur. Yogyakarta: al-Ruzz, 2004. Shihab, M. Quraish. Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, v. i. Jakarta: Lentera Hati, 2007. ________________. Wawasan al-Qur’an. Bandung: Mizan, 1997. Siroj, Said Aqil. Tasawuf sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam sebagai Inspirasi, bukan Aspirasi. Bandung: Mizan, 2006. Snijders, Adelbert. Manusia dan Kebenaran: Sebuah Filsafat Pengetahuan. Yogyakarta: Galang Press, 2010. Suseno, Franz Magnis. “Gus Dur: Bangsa Mana di Dunia Mempunyai Presiden seperti Kita,” dalam Gila Gus Dur: Wacana Pembaca Abdurrahman Wahid. Yogyakarta: LKIS, 2000. Syamsuri. “Manusia Sempurna Perspektif Murtadlâ Muthahharî,” Laporan Penelitian Dosen Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. Universitas Islam Negeri Jakarta, 2001. Syari„atî, Alî. Tugas Cendikiawan Muslim, terj. Muhammad Faishol Hasanuddin. Jakarta: YAPI, 1990. Tiahidi, Simon Petrus L.. Tuhan Para Filsuf dan Ilmuwan. Yogyakarta: Kanisius, 2011. Tim Institut of Culture and Religion Studies (INCRES). Beyond the Symbols: Jejak Antropologis Pemikiran dan Gerakan Gus Dur. Bandung: INCRES, 2000. Tjahjadi, Lili. “Ateisme Sartre; Menulak Tuhan Mengiyakan Manusia,” dalam Filsafat Eksistensialisme Jean-Paul Sartre. Yogyakarta: Kanisius, 2003. Wahid, Abdurrahman. Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia Transformasi Kebudayaan. Jakarta: The Wahid Institute, 2007. dan ___________________. Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama, Masyarakat, Negara dan Demokrasi. Jakarta: The Wahid Institute, 2006. ___________________. Menggerakkan Yogyakarta: LKIS, 2007 Tradisi: Esai-esai Pesantren. ___________________. “Pemikiran Islam yang Brilian,” dalam Badiatul Rozikin, dkk, 101 Jejak Tokoh Islam Indonesia. Yogyakarta: E-Nusantara, 2009. 87 ___________________. “Pengembangan Ahlussunah wa al-Jamaʻah di Lingkungan Nahdlatul Ulama”, dalam Said Aqil Siradj, Ahlussunnah wa al-Jamaʻah: Sebuah Kritik Historis. Jakarta: Pustaka Cendekia Muda, 2008. ___________________. Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan. Depok: Desantara, 2001. ___________________. Prisma Pemikiran Gus Gur. Yogyakarta: LKIS, 2010. ___________________. Tuhan tidak Perlu Dibela. Yogyakarta: LKIS, 2010. Wahid, Yenny Zannuba. “Gus Dur: Seorang Pejuang Kemanusiaan,” Rumadi (ed), Damai Bersama Gus Dur. Jakarta: Kompas, 2010. Yahya, Iip D.. Gus Dur: Berbeda Itu Asyik. Yogyakarta: Kanisius, 2008.