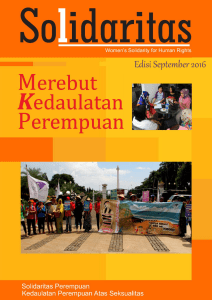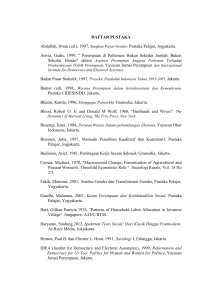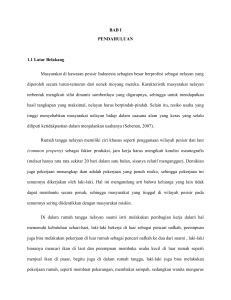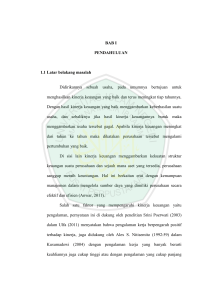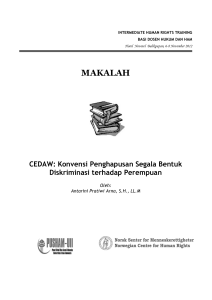1 BAB I PENGANTAR A. Latar Belakang Masalah
advertisement

BAB I PENGANTAR A. Latar Belakang Masalah Keterlibatan perempuan dalam sejarah perfilman di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kehadirannya dalam seni pertunjukan yang telah lebih dulu berkembang. Sebelum pertunjukan film dikenal masyarakat luas di Hindia Belanda, perempuan telah lebih dulu bersinggungan dalam dunia seni pertunjukan. Kehadiran mereka nampak dalam perannya sebagai penari dalam beragam tradisi lokal semacam tayuban1 hingga pemain sandiwara dalam komedie stamboel maupun toneel melayu yang populer di kalangan masyarakat perkotaan Hindia Belanda sekitar awal abad XX. Hindia Belanda pada masa itu tengah memasuki jaman kemajuan dimana beragam kebijakan pemerintahan kolonial mulai dari penghapusan Tanam Paksa, liberalisasi ekonomi hingga Politik Etis membawa dampak terhadap perkembangan sarana dan infrastruktur modern yang memiliki arti penting bagi perkembangan kehidupan masyarakatnya.2 1 Merupakan semacam tradisi di kalangan priyayi yang diadakan setelah upacara – upacara penting yang berhubungan dengan keraton, dan berlangsung sesudah pukul satu malam sampai pagi keesokan harinya. Ketika nayub seorang lelaki biasanya menari dengan ronggeng dan bisa memberi uang dengan cara menyelipkannya ke dalam kemben si ronggeng. Kuntowijoyo, Raja, Priyayi, dan Kawula: Surakarta 1900-1915 (Yogyakarta: Ombak, 2004), hlm. 80-81. 2 Pendirian rumah gadai pemerintah, pelayanan kredit rakyat, pelayanan informasi, peningkatan pertanian, opiumregie (monopoli candu oleh negara), pelayanan kesehatan, pelayanan pos, telegram, telepon, kereta api, dan pendidikan bagi kaum pribumi menjadi bagian dari aktivitas pemerintahan kolonial demi kemajuan negeri jajahan.Takashi Shiraishi, Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926 (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hlm. 36. 1 Peningkatan infrastruktur dan beragam layanan yang tersedia di beberapa kota di Pulau Jawa pada gilirannya menarik gelombang urbanisasi sehingga menyebabkan perubahan dalam struktur masyarakat Hindia Belanda. Kelas priyayi baru muncul sebagai kelas menegah yang berperan besar dalam membentuk masyarakat konsumen dan menyokong perubahan gaya hidup masyarakat pribumi di berbagai kota besar di Hindia Belanda sejak awal abad XX.3 Perkembangan kota sebagai titik pertemuan antara masyarakat dari beragam latar belakang menyediakan ruang bagi terjadinya pembauran beragam kebudayaan dimana kebudayaan tersebut saling berinteraksi dan beradaptasi dengan berbagai unsur budaya lokal. Keadaan semacam ini pada gilirannya memiliki arti penting bagi manusia dalam hubungannya dengan kesenian.4 Munculnya seni pertunjukan komedie stamboel, toneel, hingga sandiwara modern menjadi salah satu bukti meluasnya kebudayaan mestizo di kalangan masyarakat perkotaan yang terpengaruh derasnya arus modernisasi yang menyebar dan menggeser kebudayaan feodal yang berpusat pada keraton secara perlahan.5 Jenis-jenis pertunjukan tersebut hadir di tengah masyarakat perkotaan yang membutuhkan hiburan dalam bentuk yang baru karena kultur perkotaan yang 3 Bedjo Riyanto, Iklan, Surat Kabar dan Perubahan Masyarakat di Jawa Masa Kolonial 1870-1915 (Yogyakarta:Tarawang, 2000), hlm. 4. 4 Cepatnya perubahan dan meluasnya kontak dengan kebudayaan barat membawa pengaruh besar terhadap kebudayaan dan kesenian di Hindia Belanda, Wertheim bahkan menganggap bahwa keberlangsungan keadaan tersebut memicu peniruan seenaknya terhadap apa yang dianggap pada masa itu sebagai kebudayaan barat. Seperti yang dikutip oleh Salim Said dalam Profil Dunia Film Indonesia (Jakarta: Grafiti Pers, 1991), hlm.14. 5 Lihat W.F. Wertheim, Masyarakat Indonesia dalam Transisi: Studi Perubahan Sosial (Yogyakarta:Tiara Wacana, 1999), hlm. 243. 2 dinamis tidak lagi memungkinkan mereka untuk menikmati pertunjukan seni tradisional semacam wayang yang diketahui memakan banyak waktu. Rombongan Miss Riboet’s Orion dan Dardanella merupakan rombongan yang sempat merajai dunia pementasan sandiwara, meskipun di tengah jalan kepopulerannya harus bersaing dengan pertunjukan film yang mulai berkembang. Peningkatan produksi film yang dihasilkan oleh beberapa studio film di Hindia Belanda disamping distribusi film impor yang masif menjadi salah satu ancaman bagi kelangsungan hidup seni pertunjukan keliling tersebut. Bagi para seniman sandiwara, menurunnya pamor sandiwara ketika itu tidak banyak memberikan pilihan, beberapa diantaranya memilih untuk beralih ke dunia film yang dirasa lebih menjanjikan. Nama – nama seperti Roekiah, Ratna Asmara, Soekarsih, Wolly Sutinah, Fifi Young, dan Dewi Mada merupakan cikal bakal pemain film yang lahir dari dunia panggung sandiwara. Kecenderungan menarik pemain dari rombongan sandiwara untuk bermain dalam film - film hasil produksi Hindia Belanda menjadi ciri khas yang menonjol dalam perfilman Hindia Belanda menjelang akhir tahun 1930-an. Strategi semacam ini terbukti sukses meraih jumlah penonton yang signifikan namun di satu sisi justru menjadi penyumbang terbesar bagi kemunduran dunia sandiwara di Hindia Belanda.6 Tidak dapat diungkiri bahwa sejak masa kolonial, film mulai mengambil perannya dalam proses sosialisasi dan konstruksi stereotipe perempuan yang seksis. Gambaran mengenai perempuan yang beroperasi di wilayah domestik 6 Andjar Asmara, “Crisis Toneel di Indonesia”, dalam Doenia Film Tahun I, No.8, 1941, hlm. 35. Pertjatoeran 3 menjadi stereotipe yang paling sering ditemui dalam layar film. Sosialisasi citra perempuan yang sepertinya rela menanggung beratnya beban penderitaan akibat ulah dan perlakuan buruk suaminya dapat dengan mudah ditemui pada periode tersebut, salah satunya melalui “Eulis Atjih” yang diproduksi tahun 1927 dan menjadi salah satu dari sekian banyak representasi perempuan ideal pada masanya. Film yang diangkat dari roman “Tjarios Eulis Atjih” karangan Joehana atau lebih dikenal dengan Achmad Bassach ini berkisah mengenai penderitaan dan kesetiaan yang dituntut dari seorang istri terhadap suami yang pernah meninggalkannya dan gemar hidup berfoya – foya.7 Film tersebut seolah membuka jalan bagi kecenderungan maraknya film bertema serupa yang mengisahkan lika – liku kehidupan perempuan sebagai tema cerita yang menjamur pada masanya. Tidak lama berselang, berturut-turut lahir film serupa yang mengetengahkan kehidupan perempuan sebagai daya tarik utamanya.8 Alihalih melibatkan perempuan sebagai pemeran utama, namun yang ada justru menyajikan dan melanggengkan stereotipe domestik perempuan yang diidealkan sedemikian rupa. Sebagai konsekuensinya, kehadiran perempuan dalam film 7 Film ini masih merupakan film bisu yang diproduksi oleh Java Film Company dan disutradarai G.Kruegers. Film ini mencetak sukses sehingga film dengan judul yang sama dibuat kembali di tahun 1954. Disarikan dari J.B. Kristanto, Katalog Film Indonesia 1926 – 2007 (Jakarta: Nalar, 2007), hlm.1. 8 Sebut saja Lily Van Java, Njai Dasima I, II,III, Melati Van Agam I, II, Boenga Roos dari Tjikembang hingga Roekihati. Kesemuanya diproduksi dan disutradai oleh warga Tionghoa yang sebagian besar menguasai produksi film jaman kolonial. Dari sekitar 100-an buah film yang diproduksi jaman kolonial, setidaknya sekitar 20-an buah film cerita (sebagian besar merupakan film hasil adaptasi dari karya sastra modern, baik pribumi maupun Cina) yang secara gamblang memasang nama tokoh utama perempuannya sebagai judul filmnya sepanjang tahun 1926 – 1950. J.B. Kristanto, ibid., hlm. 1 – 13. 4 cenderung dikonstruksikan dalam beragam bentuk pencitraan perempuan yang tidak seimbang dan terkonstruksi secara sosial budaya. Tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada representasi perempuan di dalam layar film, persepsi masyarakat mengenai keterlibatan perempuan dalam perfilman pada periode awal cenderung disamakan dengan stigma “perempuan tontonan”. Kebutuhan akan sosok perempuan yang tetap diperlukan sebagaimana film membutuhkan sosok lelaki dalam penggambaran visual dan narasinya tidak serta merta membuat posisi perempuan lebih beruntung dibandingkan dengan rekan laki-lakinya. Perempuan yang terlibat di dalamnya atau katakanlah menjadikan dirinya sebagai pihak yang sengaja memperbolehkan dirinya ditonton menurut pandangan masyarakat dianggap bukanlah perempuan baik- baik sehingga pantas dipandang rendah derajatnya.9 Para perempuan ini harus membiasakan diri dengan stigma tledek, semacam julukan yang berkonotasi negatif yang berangkat dari kepopuleran tayuban yang ditujukan bagi perempuan yang menekuni dunia pertunjukan. Dalam periode selanjutnya, stigma tersebut terus berkembang seiring dengan kepopuleran pertunjukan sandiwara yang turut membawa serta stigma anak wayang yang terisolir dalam kehidupan bermasyarakat. Persepsi sosial masyarakat semacam itu bukannya tidak mungkin menjauhkan bahkan mempersempit akses perempuan dalam beragam aktifitas keseniannya. 9 “Wanita dalam Sedjarah Film Indonesia” dalam Aneka edisi 4 tahun ke1, 15 April 1950, hlm. 9. 5 Sementara itu, keterlibatan mereka yang menjanjikan popularitas tentunya berdampak langsung terhadap peningkatan karir dan ekonomi, sesuatu yang sangat jarang sekali bisa diperoleh perempuan pada masa tersebut. Mobilitas vertikal10 dalam struktur masyarakat tak pelak dialami oleh para aktris yang berkecimpung dalam industri perfilman. Hal tersebut pada gilirannya mampu membawa mereka memasuki transformasi peran yang belum pernah terjadi pada masa sebelumnya di sepanjang sejarah perfilman Indonesia. Nama besar dan pengalaman yang diperoleh bersamaan dengan kemapanan secara finansial mendorong mereka untuk mengembangkan karir di industri perfilman dengan beragam cara, salah satunya adalah dengan merambah peran baru sebagai seorang sutradara bahkan produser film melalui sejumlah perusahaan film yang didirikannya. Meskipun demikian, mobilitas vertikal yang dirasakan oleh para perempuan ini tidak serta merta menjauhkannya dari segala macam hambatan untuk bersaing dengan rekan lelakinya dalam industri perfilman Indonesia periode awal. Hal tersebut menjadi akibat dari adanya mobilitas sosial yang selain mengakomodir penyesuaian juga mampu memunculkan konflik. Konflik yang muncul kemudian tak jarang hadir sebagai bagian dari persinggungan dengan sistem normatif dan nilai yang berlaku dalam masyarakat tradisional Indonesia, dimana kultur Jawa menjadi sedemikian dominannya. Dalam nilai-nilai tradisi Jawa, masyarakatnya akrab mengenal konsep macak 10 Mobilitas vertikal atau social climbing merupakan salah satu unsur dari gerak atau mobilitas sosial yang berupa perubahan, pergeseran atau peningkatan status dan peran yang dialami anggota masyarakat yang sebagian besar dipengaruhi oleh beragam faktor seperti perubahan kondisi sosial dan budaya masyarakatnya. Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 220. 6 (pandai merias diri), manak (kemampuan menghasilkan keturunan) dan masak (di dapur) dalam kehidupan para perempuannya. Melalui konstruksi peran ideal semacam inilah, peran perempuan menjadi tereduksi sebatas area domestik yang kemudian mempengaruhi kedudukan, peran, serta tingkah laku para perempuan, sehingga berpeluang menciptakan pembagian kerja secara seksual dengan membedakan pekerjaan - pekerjaan mana yang dianggap pantas dan tidak pantas bagi perempuan yang hidup dalam budaya tersebut. Dengan demikian, kehadiran perempuan dalam dunia perfilman terkesan problematis karena memiliki dualitas posisi yang tak terelakkan dan bahkan seringkali dianggap kontroversial. Sejak periode kolonial perempuan menjadi dominan kehadirannya dalam industri perfilman sebagai tontonan karena mereka secara praktis hanya dilibatkan sebagai pihak yang ditonton dan belum menjadi pihak yang memiliki andil dalam proses produksi sebuah film. Oleh sebab itulah ketenaran bintang film perempuan menjadi teramat dominan dan populer di kalangan masyarakat bahkan hingga saat ini, meskipun sebagian besar peran yang dimainkannya di dalam layar justru melanggengkan dan memperkuat peran gender perempuan. Kehadiran perempuan yang lebih dinilai dari penampilan fisik dibanding kemampuannya dalam berakting oleh masyarakat tak jarang menjadikannya sosok kontroversial dalam dunia perfilman di Indonesia. “Saya tidak akan memerosotkan kesenian, melainkan hendak melenyapkan pandangan – pandangan kolot yang masih terdapat dalam kesenian Indonesia.”11 11 “Peristiwa Nurnaningsih”, dalam Kentjana Oktober 1954, hlm.24. No.6. Thn.II, edisi 30 7 Demikian pernyataan Nurnaningsih dalam menanggapi berita mengenai peredaran foto vulgar dirinya yang menjadi ladang pemberitaan di berbagai media cetak Indonesia. Pernyataan tersebut dengan segera memancing reaksi masyarakat dan menjadikannya aktris yang kontroversial sekaligus populer di sekitar tahun 1950an. Menurut masyarakat, perilakunya dianggap mencederai norma adat ketimuran yang selama ini diagungkan dan berdampak secara langsung terhadap penurunan karir keartisannya. Pasca kemerdekaan ketika Indonesia sebagai sebuah negara baru terbentuk, semangat nasionalisme yang menggebu – gebu hadir dari sebagian besar masyarakatnya. Kita perlu mengingat bagaimana keoptimisan dari kalangan seniman untuk menjadikan perfilman nasional jauh lebih menampakkan “wajah Indonesia-nya” sekaligus menjadikannya tuan rumah di negerinya sendiri bukanlah suatu perkara yang mudah. Kutipan diatas seakan menjadi pengingat bahwa dalam perjalanan film Indonesia ketika tujuan mempertahankan semangat nasionalisme dengan menjunjung tinggi nilai – nilai ketimuran harus berbenturan dengan pengaruh kapitalisme dan modernisme yang menjangkiti masyarakat. Dengan demikian perempuan berada dalam posisi tarik menarik di antara beragam kepentingan yang menyebabkan posisinya menjadi subordinat dalam struktur perfilman tanah air. “Jarang ada kritikus yang mau mendiskusikan soal itu, wajah wanita tidak pernah jadi masalah penting dalam perfilman kita”.12 12 Seperti yang ditulis Krishna Sen ketika mewawancarai Misbach Yusa Biran sekitar tahun 1981 dalam “Wajah Wanita dalam Film Indonesia: Beberapa Catatan”, Prisma edisi 7 (Jakarta: LP3ES, Juli 1981), hlm. 32. 8 Kutipan pernyataan Misbach Yusa Biran tersebut seakan menegaskan betapa perempuan menjadi subordinat dalam dunia perfilman tanah air yang maskulin. Perfilman seolah-olah hanya dibangun oleh tokoh laki-laki saja tanpa sedikitpun mempertimbangkan peran perempuan yang terlibat di dalamnya. Hal yang sama juga kembali dirasakan oleh Sen ketika ia merasa kesulitan menemukan rujukan tulisan yang berbicara mengenai hubungan perempuan dengan film Indonesia. Menurutnya hal tersebut sangat ironis mengingat dari sedemikian banyaknya jumlah tulisan mengenai film yang ada dan tersimpan di Sinematek dalam kurun waktu tersebut, tidak satupun ditemukan pembahasan mengenai perempuan dalam perfilman Indonesia.13 Terkait absennya perempuan dalam sejarah perfilman bukan semata-mata berbicara mengenai penting atau tidaknya mereka untuk dibicarakan melainkan lebih mencerminkan bagaimana sudut pandang patriarkis menjadi sangat dominan dalam sebagian besar aspek kehidupan masyarakatnya. Sudut pandang ini tidak mengakomodasikan kesetaraan bahkan cenderung berpretensi menomorduakan perempuan dalam segala macam bentuk relasi gender sehingga perempuan menjadi terlupakan untuk diperhitungkan seberapapun besaran kontribusinya. B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini akan berbicara mengenai transformasi peran perempuan dalam sejarah perfilman Indonesia 1926- 13 Ibid. 9 1971. Pertanyaan – pertanyaan pokok yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah posisi dan peran perempuan dalam industri perfilman Indonesia sejak 1926 - 1971? 2. Mengapa terjadi pergeseran peran perempuan dan bagaimanakah bentuk – bentuk pergeseran tersebut? 3. Bagaimana respon masyarakat terkait penampilan dan perilaku perempuan dalam perfilman sepanjang periode tersebut? Film dan pertunjukannya hadir di hadapan publik Hindia Belanda sebagai bagian dari perubahan sosial budaya yang mewarnai Hindia Belanda sejak awal abad XX. Perubahan sosial budaya yang terjadi pada masa tersebut tidak hanya terbatas pada perubahan tata ruang dan infrastruktur di perkotaan Hindia Belanda saja, namun lebih mengarah pada bagaimana budaya modern itu diterapkan mulai dari liberalisasi ekonomi, restrukturisasi birokrasi kolonial, pendidikan, gaya hidup, hingga perkembangan teknologi dan media massa yang tergolong pesat pada jamannya. Fokus dalam penelitian ini adalah perempuan dalam sejarah perfilman Indonesia. Selama ini, perbincangan mengenai hubungan perempuan dengan perfilman dapat dikaji melalui dua jenis kajian, pertama adalah kajian yang membicarakan hubungan perempuan terkait representasi peran yang dihasilkan melalui sejumlah film yang beredar. Kajian semacam ini lebih mengarah pada persoalan representasi perempuan sebagai bagian dari konstruksi gender yang seringkali merugikan perempuan dalam penggambarannya di film. Sementara itu, 10 yang kedua adalah perbincangan mengenai posisi dan peran perempuan secara historis dalam industri perfilman yang mampu mengungkap beragam bentuk transformasi peran ke arah yang belum pernah terjadi pada periode sebelumnya di Indonesia. Untuk itulah dalam penelitian ini, penulis tidak berpretensi mengungkap bagaimana perempuan direpsentasikan melalui film – film Indonesia yang beredar sekitar tahun 1926-1971. Berkenaan dengan fokus penelitian tersebut, maka lingkup temporal akan dimulai sekitar tahun 1926 dan dibatasi sekitar tahun 1971. Tahun 1926 dipilih berdasarkan alasan belum adanya kajian yang secara spesifik dan komprehensif mendeskripsikan peranan perempuan secara historis dalam perfilman sepanjang periode tersebut. Tahun 1926 juga dipilih berdasarkan fakta historis yang mengungkapkan bahwa sejak tahun tersebut telah berlangsung proses produksi sebuah film lokal di Hindia Belanda melalui kegiatan produksi film berjudul “Loetoeng Kasaroeng”(1926) yang dengan segera diikuti oleh produksi sejumlah film lainnya. Dalam proses produksi tersebut ditemukan pula fakta bahwa perempuan sudah ikut dilibatkan sebagai pemain dalam layar lebar, maka berdasarkan tahun inilah diharapkan rekam jejak keterlibatan perempuan sekiranya mulai dapat ditelusuri. Kajian ini selanjutnya akan diakhiri pada masa awal era Orde Baru yaitu sekitar tahun 1971 dikarenakan pembahasan mengenai perempuan dalam film Indonesia sejak tahun itu sudah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu sebagai akibat dari kesadaran mengenai gender dalam film yang bergulir secara sporadis di berbagai media cetak saat itu. Selain itu, secara statistik terdapat 11 penurunan jumlah perempuan sutradara yang berperan di balik layar dibandingkan pada periode sebelumnya. Jika pada periode pasca kemerdekaan diketahui terdapat tiga orang sebagai pionir sutradara perempuan di Indonesia; Ratna Asmara, Chitra Dewi, dan Sofia W.D, namun sejak tahun 1971 diketahui hanya dua perempuan sutradara yang mampu berkiprah di industri perfilman nasional hingga akhir periode 1970-an, yaitu Sofia W.D dan Ida Farida.14 Oleh sebab itu ada baiknya penulis membatasi kajian ini sampai pada tahun tersebut. C. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan transformasi peran yang berhasil dijalani perempuan dalam sejarah perfilman Indonesia sepanjang periode 19261971. Dengan begitu, penelitian ini diharapkan mampu menampilkan perempuan sebagai bagian dari industri perfilman Indonesia yang ikut ambil bagian dalam perkembangan perfilman nasional. Secara praktis penelitian ini juga diharapkan memiliki kontribusi dalam penulisan sejarah perfilman Indonesia. D. Tinjauan Pustaka Dalam ranah akademis terdapat beberapa karya yang berkaitan dengan tema perfilman Indonesia. Penelitian mengenai perfilman Indonesia yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu pada umumnya memiliki kecenderungan beberapa tema kajian. Tema kajian pertama adalah yang kajian yang berorientasi pada pendekatan sosio-historis melalui pembahasan mengenai dinamika perfilman 14 Disarikan dari Sinematek, Apa Siapa Orang Film 1926-1978 (Jakarta:Yayasan Artis Film dan Sinematek Indonesia, 1979). 12 nasional dari waktu ke waktu, ini adalah kajian yang paling sering dijumpai di Indonesia. Karya Salim Said dalam Profil Dunia Film Indonesia yang terbit sekitar tahun 1991,15 merupakan kajian sejarah perfilman Indonesia yang mendeskripsikan perkembangan film Indonesia sejak masa kolonial, rezim Soekarno, dan Soeharto dengan penekanan pada kekuatan militer Indonesia sekaligus menguji keterkaitannya dengan beragam faktor sosial, politik, kultural, dan ekonomi dalam membentuk wajah perfilman Nasional. Selain itu, sudut pandang kapitalis yang melingkupi perfilman Indonesia terlihat dalam karya Riyadi Gunawan. Ia mencoba mengurai kondisi perfilman Indonesia pada masa awal melalui sudut pandang tersebut. Menurutnya, kehadiran film di Indonesia sudah sejak awal dilihat sebagai barang dagangan sehingga penilaiannya berdasarkan laba - rugi semata. Beragam pertentangan abadi antara komersialisme dan idealisme yang melingkupi pembuatan film dijabarkan disini. Sebagai sebuah karya sejarah, kajian ini sebenarnya lebih banyak berbicara mengenai pergeseran orientasi pemilik modal dan pemilik bioskop yang cenderung ke arah dagang, dan itulah sebabnya mengapa mutu film saat itu bisa dikatakan jauh dari kata memadai.16 Kepentingan komersial semacam ini nampak sejalan dengan apa yang disampikan oleh Andjar Asmara, seniman yang besar dalam industri film tanah air sebelum dan sesudah kemerdekaan.17 Karya Said yang merupakan hasil analisis 15 Salim Said bahkan berani mengatakan bahwa politik adalah panglima film di Indonesia saat itu. Salim Said. op.cit. 16 Riyadi Gunawan, “Sejarah Perfilman Indonesia”, dalam Majalah Prisma Tahun XIX , (Jakarta: LP3ES, 1990). 17 Salim Said, op cit, hlm. 35. 13 sosio-historis terhadap industri perfilman Indonesia juga sudah dipaparkan dengan apik oleh beberapa nama seperti Misbach Yusa Biran18 dan Taufik Abdullah.19 Fokus terhadap aspek historis perfilman sebagai sebuah industri menjadikan beberapa kajian tersebut kurang mengangkat persoalan perempuan sebagai salah satu aspek yang ikut membentuk wajah industri perfilman tanah air. Yang kedua; kajian yang lebih mengarah pada pengaruh kuasa seperti negara terhadap film hingga analisis budaya dan representasi perempuan yang dihasilkan melalui film sejak periode Orde Baru hingga periode reformasi. Indonesian Cinema: National Culture on Screen karya Karl G. Heider, berbicara mengenai perfilman Indonesia dengan melakukan pendekatan antropologis ke berbagai persoalan perfilman tanah air dan bagaimana persoalan budaya direfleksikan dalam film-film Indonesia Orde Baru. Karl G. Heider melihat bahwa di Indonesia, film berperan besar dalam proses “imagining or constructing of an Indonesian culture”. Penelitian yang berangkat dari ketertarikan Heider terhadap film Indonesia dengan menganalisis beragam genre film untuk kemudian membandingkannya dengan film Amerika dan Eropa dalam konteks global. 18 Misbach Yusa Biran dikenal luas sebagai sutradara sekaligus bapak sejarah dan arsiparis film Indonesia karena beliau bukan saja menjadi saksi hidup tumbuh dan berkembangnya perfilman nasional. Suami dari aktris Nanny Wijaya ini juga turut berperan besar memprakarsai sekaligus memimpin Lembaga Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail (Sinematek Indonesia) periode 1975-2001 yang secara independen bercita-cita mendokumentasikan film nasional. Beliau tutup usia di umur 78 tahun, akibat sakit yang dideritanya sejak lama pada 11 April 2012. Misbach Jusa Biran, Sejarah Film 1900 – 1950 (Jakarta: Komunitas Bambu, 2009). 19 Taufik Abdullah, dkk. Film Indonesia Bagian I (1900 – 1950) (Jakarta: Dewan Film Nasional, 1993). 14 Heider hanya selintas menengok persoalan representasi perempuan melalui satu bab yang diberi judul “Feminism in a Male World: Contradictory Messages” dimana menurutnya sebagian besar perempuan dalam film digambarkan sebagai kaum yang bergantung kepada lelaki dan akan jadi hal yang mengejutkan jika itu tidak terjadi di Indonesia.20 Melalui pernyataan ini, Heider mengamini bahwa dominasi patriarkis yang diusung oleh kebudayaan Jawa sentris dalam masyarakat Indonesia menjadi sedemikian kuat mengakar secara kultural dan berdampak pada wajah perempuan dalam film yang sangat sulit berubah sehingga menjadi hal yang lumrah dan sesuatu yang tidak mengejutkan jika direpresentasikan sebagai kaum yang dipaksa kalah. Heider menilai kecenderungan film di Indonesia pasca Orde Baru dalam menggambarkan setinggi apapun perempuan berkarir, maka ia harus dikembalikan ke dalam ranah keluarga adalah sesuai dengan ideologi gender yang diinginkan negara, mereka seolah dipaksa untuk kembali ke ranah domestik keluarga di akhir cerita. Representasi tersebut secara kultural ingin menegaskan bahwa perempuan dalam film Indonesia Orde Baru adalah perempuan yang pasif dan menjadi kelompok terpinggirkan serta tidak berperan penting dalam film karena hanya dijadikan pemanis bagi dunia perfilman yang diciptakan lelaki. Penelitian yang menfokuskan diri pada perempuan dalam film Indonesia Orde Baru juga terlihat melalui kajian karya Sita Aripurnami. Melalui kajian ini diuraikan bagaimana film pada akhir tahun 1980-an menggambarkan perempuan 20 Karl. G. Heider, Indonesian Cinema: National Culture on Screen (Honolulu: University of Hawaii Press, 1991). 15 melalui enam buah film unggulan Piala Citra tahun 1988 dan 1989.21 Sita Aripurnami mendiskusikan ragam dikotomi gender yang direpresentasikan dalam film –film tersebut. Hasilnya adalah perempuan direpresentasikan secara dikotomis antara perempuan baik dan jahat, perempuan yang tau aturan dan menyimpang, hingga perempuan amoral yang perlu dihukum di akhir cerita. Aripurnami juga menelusuri peran perempuan dalam film masa awal, dimana sebagian besar perempuan sebagai aktris ditempatkan hanya sebagai figuran. Jika pun mereka mendapatkan peran sebagai bintang utama, itu pasti berkaitan dengan peran domestiknya yang sebatas rumah. Melalui perspektif kajian komunikasi massa dan ekonomi politik, Krishna Sen mengungkapkan dinamika dan perentangan kepentingan ideologis dalam industri film Indonesia. Persoalan kekuasaan yang melingkupi sinema Indonesia dikaji lebih lanjut untuk menafsirkan arah feminisme dalam film pada masa Orde Baru. Sen melihat sinema Indonesia dari konteks sosial politik kemudian membaginya ke dalam tiga periode dan berhenti di tahun 1994, ia kemudian menganalisis pergeseran representasi perempuan tahun 1980-an dan konotasi yang muncul dari representasi itu.22 Pembahasan secara kritis terhadap representasi perempuan dalam beberapa film Orde Baru sekaligus mendeskripsikan stereotipe 21 Sita Aripurnami, “Perempuan Pada Film”, dalam Prisma Tahun XIX, (Jakarta: LP3ES, 1990). 22 Krishna Sen, Kuasa dalam Sinema: Negara dan Masyarakat (Penerbit Ombak: Yogyakarta, 2009). 16 peran gender yang ada dalam film Indonesia menjadikan kajian ini memiliki kontribusi tersendiri dalam kajian gender dengan film sebagai objek materialnya. Beragam kajian tersebut tentu dapat membantu mendeskripsikan perkembangan film sebagai sebuah industri berkembang di Indonesia, meskipun demikian kajian yang disumbangkan oleh para pemikir di atas masih bersifat general jika dikaitkan dengan posisi dan peranan perempuan dalam perfilman Indonesia sejak periode kolonial hingga awal 1971 yang tidak bisa digeneralisir begitu saja sebagai suatu entitas yang sama dari satu periode ke periode lainnya. Kajian yang banyak ditemui jika berbicara mengenai perempuan dalam film hampir selalu diarahkan ke dalam bentuk kajian representasi perempuan dalam film periode Orde Baru dan sesudahnya, mengingat persoalan representasi perempuan memang menjadi bidang kajian dan pemikiran cultural studies yang cukup populer dan sedang berkembang di Indonesia. Berdasarkan pemikiran itu, maka disimpulkan bahwa sepengetahuan penulis belum dijumpai studi sejarah yang berusaha mendeskripsikan peran perempuan dalam sejarah perfilman Indonesia sejak periode kolonial hingga pasca kemerdekaan. E. Kerangka Konseptual Kuntowijoyo melihat tema mengenai peran perempuan dalam berbagai sektor sosial ekonomi bisa ditemukan dalam berbagai bentuk ragamnya masingmasing yang berupaya menyuarakan perempuan sebagai pihak subordinat yang jarang nampak dalam penulisan sejarah androsentris. Penulisan mengenai peranan perempuan dalam berbagai sektor tersebut diharapkan dapat digunakan untuk 17 memperjelas peranan perempuan dalam bidang sosial, kultural hingga ekonomi yang selama ini masih minim dilakukan oleh sejarawan.23 Atas dasar inilah maka perlu dipahami konsep mengenai peran dan gender dalam penulisan sejarah ini. Dalam industri media, persoalan yang kerap kali muncul dalam perbincangan mengenai peran perempuan adalah adanya indikasi ketidakmampuan perempuan untuk berperan secara dominan di bidang produksi. Mengenai persoalan tersebut, Erica Carter menyatakan bahwa perempuan menjadi marjinal dan subordinat dalam bidang “budaya kerja maskulin”, karena mereka telah dibentuk oleh ideologi masyarakat patriarki untuk menjadi dominan di bidang subordinat yaitu sebagai objek tontonan atau konsumsi, disinilah pria identik dengan produktivitas di bidang produksi, sedangkan perempuan menjadi identik dengan konsumsi, sehingga tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan dari kondisi tersebut karena sudah dianggap lumrah.24 Marginalisasi perempuan dalam bidang produksi dan dominasi mereka sebagai objek tontonan inilah yang sering menjadi ideologi utama bagi media – media dimanapun, termasuk film di Indonesia. Dengan kata lain, alih-alih melibatkan perempuan dalam film, ketimpangan ideologis antara lelaki dan perempuan dalam praktik sosiokultural masyarakat akan dikesankan hilang karena 23 Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah: Edisi Kedua, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 120. 24 Seperti yang dikutip oleh Yasraf Amir Piliang, “Masih Adakah Aura Wanita di Balik Euphoria Media” dalam Idi Subandy Ibrahim (ed.), Wanita dan Media: Konstruksi Ideologi Gender dalam Ruang Publik Orde Baru (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), hlm. xiii. 18 mereka dianggap sudah ikut ambil bagian di dalamnya.25 Padahal, minimnya keterlibatan perempuan dalam sejarah perfilman tanah air sejak periode awal berhasil membangun persepsi bahwa dunia film adalah dunia maskulin yang hanya dibangun oleh laki-laki, maka ketika perempuan terjun ke dalamnya, perannya menjadi tidak nampak, bahkan ada kecenderungan dari mereka untuk ikut mengadopsi cara pandang yang sama dengan secara sadar maupun tidak menyetujui sistem nilai yang dianut. Inilah yang kemudian menjadikan persoalan perempuan dan gambarannya dalam film menjadi menarik untuk dipertanyakan. Peran (role) adalah konsep yang dinamis dan selalu berkaitan dengan kedudukan atau status.26 Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Kedudukan dan peran tidak dapat dipisahkan, karena saling tergantung antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, tak ada peran tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peran. Hal itu sekaligus berarti bahwa kedudukan membawa serta peran peran tertentu sekaligus menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.27 Dalam konteks ini yang akan dibicarakan adalah peran yang dijalankan oleh perempuan dalam industri perfilman Indonesia. Kedudukan atau posisi perempuan dalam 25 Ikwan Setiawan, Perempuan dalam Layar Bergerak: Representasi Perempuan dan Pertarungan Ideologis dalam Film Indonesia Era 2000-an (Analisis Semiotika Mitos Barthesian dan Wacana Foucouldian), Tesis tidak diterbitkan (Yogyakarta: S2 Kajian Media Budaya UGM, 2008), hlm.61. 26 27 Soerjono Soekanto, op.cit., hlm. 217. Ibid., hlm. 213. 19 perfilman Indonesia tentu saja membawa serta peran di dalamnya, namun kedudukan perempuan dalam film yang seringkali dilihat secara hierarkis dimana laki-laki berada pada kedudukan dominan sedangkan perempuan subordinat menjadikan perannya dalam dunia perfilman tidak dianggap penting. Simone de Beauvoir mengungkapkan bahwa realitas sosial yang menempatkan perempuan sebagai the second human being yang ditempatkan di bawah superioritas laki-laki telah berdampak luas dalam kehidupan bermasyarakat.28 Dalam dunia perfilman hal ini juga terasa, absennya perempuan dalam perfilman tanah air semakin dipertegas dengan minimnya keterlibatan perempuan dan rendahnya pengakuan terhadap perempuan dalam industri film. Sita Aripurnami dalam penelitiannya mengenai gambaran perempuan dalam film pasca Orde Baru menemukan bahwa ada kecenderungan beberapa perempuan yang menekuni bidang produksi di balik layar setelah tahun 1965 harus mengadopsi cara pandang yang sama dengan standar laki-laki sehingga representasi perempuan yang dihasilkannya pun sejalan dengan ideologi patriarkis agar karyanya dapat sukses dan diterima di kalangan perfilman dan masyarakat.29 Tidak hanya ini, beberapa peneliti sinema Indonesia bahkan menyetujui bahwa 28 Anggapan bahwa perempuan sekedar pelengkap yang diciptakan dari dan untuk kepentingan laki-laki berakibat perempuan hanya boleh ditempatkan di ranah domestik saja, sedangkan laki-laki berada di ranah publik. Simone de Beauvoir, The Second Sex: Kehidupan Perempuan, Indonesia. Terj. Toni B. Febriantono, dkk. (Jakarta: Pustaka Prometea, 2003), hlm. 14. 29 Sita Aripurnami, “Cengeng, Cerewet, Judes, Kurang Akal, dan BukaBukaan: Gambaran Perempuan dalam Film Indonesia” dalam Idi Subandi Ibrahim,ed., Wanita dan Media Konstruksi Ideologi Gender dalam Ruang Publik Orde Baru, op.cit., hlm. 296. 20 dominasi patriarki menjadi sangat kental meliputi kultur film yang ada di Indonesia, dan sulit untuk berubah.30 Sudut pandang laki-laki dalam film dapat ditelusuri melalui dominannya peran laki-laki sebagai penentu kebijakan sehingga melalui film, mereka dapat membentuk kembali peran – peran gender tertentu terhadap perempuan yang sesuai dengan harapannya. Untuk itulah diperlukan kesadaran dalam menelaah keterkaitan antara perempuan dan sinema melalui pendekatan gender. Pendekatan ini digunakan untuk mencoba melihat perempuan sebagai aspek dalam arus utama sejarah sehingga tidak mengisolasinya sebagai suatu sejarah yang androsentris. Dengan demikian akan ditemukan beragam akses yang dimiliki perempuan dalam sejarah perfilman berupa tingkat partisipasi atau kontribusi perempuan yang menghasilkan beragam peranan di dalamnya. Berbicara tentang gender berarti berbicara tentang relasi yang terjalin antara laki-laki dan perempuan, untuk itulah diperlukan pemahaman yang mendasar mengenai perbedaan antara konsep seks atau jenis kelamin dengan gender yang seringkali mengalami pengaburan makna. Ann Oakley memandang bahwa perbedaan seks berarti perbedaan atas dasar ciriciri biologis, terutama yang menyangkut prokreasi (hamil, melahirkan dan menyusui), sedangkan perbedaan gender adalah perbedaan simbolis atau sosial 30 Seperti yang diungkapkan oleh Krishna Sen dalam Indonesian Cinema: Framing the New Order (London: Zed Books, 1994). Karl G.Heider, Indonesian Cinema: National Culture On Screen, op.cit. Intan Paramaditha, “Pasir Berbisik and New Women’s Aesthetics in Indonesian Cinema” http://www.ejumpcut.org/archive/jc49.2007/PasirBerbisik/index.html, diakses sekitar April 2011. Sita Aripurnami “Penampilan Perempuan dalam Gambar Hidup: Cermin Dominasi Cara Pandang Patriarki” dalam Idi Subandi Ibrahim,ed., Wanita dan Media Konstruksi Ideologi Gender dalam Ruang Publik Orde Baru, op.cit., hlm.223. 21 yang berpangkal kepada perbedaan seks, tetapi tidak selalu identik dengannya.31 Dengan begitu, gender merupakan kategorisasi yang memisahkan laki-laki dan perempuan atas dasar asumsi - asumsi perilaku, nilai, sikap, dan kepercayaan yang seringkali maknanya dikontraskan dengan seks yang lebih mengacu pada perbedaan secara biologis.32 Dewasa ini muncul semacam doktrin bahwa apa yang sesungguhnya merupakan gender justru dianggap sebagai kodrat sehingga dalam penerapannya tidak boleh dipertukarkan. Ini kemudian akan berpengaruh terhadap peranan dan pekerjaan mana saja yang dianggap pantas atau tidak pantas dimainkan baik oleh lelaki maupun perempuan sebagai anggota masyarakat. F. Sumber Penulisan dan Metode Penelitian Salah satu dari tujuan ilmu sejarah adalah untuk memenuhi rasa ingin tahu mengenai fenomena yang terjadi di masa lalu, tentang bagaimana deskripsi peristiwa, penyebab peristiwa itu terjadi, serta perkiraan implikasi atau dampak peristiwa tersebut terhadap bidang kehidupan.33 Tujuan studi ini adalah untuk mencapai penulisan sejarah, maka upaya merekonstruksi masa lampau dari obyek 31 Ann Oakley, seorang ahli sosiologi dari Inggris merupakan orang yang pertama kali melakukan pembedaan istilah gender dan seks. Lebih jauh periksa Ratna Saptari, Brigitte Holzner, Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial sebuah pengantar studi Perempuan, (Jakarta: Kalyanamitra, 1997), hlm. 89. 32 Konsep gender itu sendiri dimaksudkan untuk melihat perbedaan yang tidak alami atau perbedaan yang dibentuk secara sosial budaya dan bukan lagi terletak pada perbedaan secara biologis yang sifatnya dapat dipertukarkan dan berubah – ubah dari waktu ke waktu. Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm.7-8. 33 Rustam E. Tamburaka, Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat dan IPTEK (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), hlm. 5. 22 yang diteliti itu ditempuh melalui metode penelitian sejarah.34 Adapun penelitian ini berupa studi historis atas kontribusi perempuan dalam sejarah perfilman Indonesia. Dengan demikian, kajian ini merupakan hasil penelitian dokumentatif atas peran perempuan dalam perfilman Indonesia. Langkah pertama dalam proses penelitian sejarah adalah mencari fakta dibalik sumber data yang ada. Sumber tertulis didapatkan penulis dari sejumlah arsip, majalah, surat kabar, buku-buku teks, tesis, dan jurnal ilmiah. Pada proses ini penulis melakukan pencarian terhadap sumber – sumber sejarah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan perempuan dalam perfilman indonesia periode pasca kemerdekaan. Penulis memusatkan kegiatan pencarian sumber di beberapa tempat yang memungkinkan dimana sumber data yang akan dipakai itu disimpan. Penelusuran sumber arsip kolonial yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan kolonial terhadap perfilman dapat ditelusuri di Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia. Sumber data yang penulis temukan hanya berupa kumpulan kebijakan pemerintah dalam bidang perfilman atau Staatblads yang berisi keputusan – keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda berhubungan dengan segala bentuk kebijakan yang berkenaan dengan kegiatan penyensoran dan kebijakan pemerintah lainnya dalam hal mengatur peredaran film dan tujuan pembuatan film di jaman itu. Sumber tersebut dianggap penting karena penulis mengganggap kebijakan pemerintah Indonesia dalam 34 Secara garis besar, penelitian ini melalui tiga tahapan di mana sumber data yang akan digunakan akan berupa sumber tertulis dan tidak tertulis, kemudian bagaimana sumber tersebut didapat, dan apa yang akan dilakukan terhadap data tersebut untuk mendapatkan fakta. Dudung Abdurrachaman, Metode Penelitian Sejarah (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 91. 23 bidang perfilman hingga masa Orde Baru sebagian besar masih mengadaptasi kebijakan jaman pemerintah kolonial tersebut, termasuk dalam hal sensor. Pencarian sumber tertulis juga dilakukan di Perpustakaan Nasional untuk mencari dan menemukan artikel – artikel, majalah, dan surat kabar pada periode yang berkaitan dengan tema penelitian. Banyaknya surat kabar dan majalah film yang membahas resensi film dan para pekerjanya termasuk para artis sekitar periode 1950 hingga 1970-an, dipakai untuk melihat kondisi atau situasi yang belum tercatat dalam dokumen pemerintah. Beberapa majalah film tahun kolonial juga ditemukan disini meliputi Doenia Film, Pertjatoeran Doenia dan Film, Filmland, Panorama, surat kabar Bintang Betawi, Pewarta Soerabaia, Nieuw Weekblad, dan Preanger Post dan Pembangoenan. Beberapa surat kabar sejaman juga ditemukan seperti Aneka, Varia, Bintang Timur, Suara Merdeka, dan sebagainya. Studi pustaka juga dilakukan di beberapa perpustakaan. Pelacakan sumber tertulis dilingkup Kota Yogyakarta ditelusuri melalui perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya, Perpustakaan Kolese Ignatius, Perpustakaan Pusat UGM, Perpustakaan FISIPOL – UGM, Perpustakaan Kota Yogyakarta dan Perpustakaan Kunci Cultural Studies Yogyakarta. Selain penelusuran pustaka, penulis juga memakai metode sejarah lisan, yaitu berupa wawancara dengan sejumlah orang, terutama perempuan yang berkaitan secara langsung dan terlibat sekitar periode tersebut , walaupun banyak dari mereka yang terlibat secara langsung dalam periode awal 50-an sudah sulit ditemui hingga tidak memungkinkan untuk dilakukan wawancara. Wawancara didasarkan pada beberapa pertanyaan mengenai perjalanan hidup beserta 24 pengalaman mereka yang berkecimpung di bidang perfilman Indonesia, dan mengenai beberapa informasi mendetail yang tidak terekam dalam sumber – sumber lainnya. Sumber lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber visual berupa dari foto, baik yang didapat dari pemberian secara langsung oleh narasumber yang berhasil diwawancara maupun yang terekam dalam beberapa majalah dan surat kabar sejaman di Perpustakaan Nasional Jakarta, sedangkan hasil fotografi pada masa kolonial hanya dapat ditemui dalam situs milik KITLV. Proses berikutnya berupa kritik sumber yang berguna untuk menguji otentisitas dan kredibilitas suatu sumber. Otentisitas dimaksudkan untuk melihat apakah sumber yang telah ditemukan itu asli atau palsu, sedangkan kredibilitas dimaksudkan untuk menentukan apakah sumber itu layak atau tidak untuk digunakan dalam penelitian ini. Beberapa data yang telah berhasil terkumpul kemudian diseleksi agar kebenaran, baik isi maupun fisiknya dapat dipertanggungjawabkan sehingga menghasilkan rangkaian fakta untuk kemudian dilakukan analisis terkait permasalahan yang akan diungkap dalam penelitian ini dan disusun secara logis dan sistematis ke dalam bentuk penulisan sejarah. G. Sistematika Penulisan Demi tercapainya hasil penelitian yang sistematis serta terarah maka kerangka penulisan akan disajikan dalam lima bab yang akan dibuat secara terstruktur sehingga memudahkan pembaca dalam memahami maksud dari penelitian ini. Bab pertama merupakan bab pengantar yang di dalamnya berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konsep yang 25 dipergunakan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini diarahkan sebagai pengantar mengenai problematika perempuan dalam sinema Indonesia bahkan sejak film pertama kali dibuat. Proses penciptaan suatu film tentu saja tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial budaya dan politik dalam masyarakat karena bagaimanapun juga film tidak pernah lahir dari kondisi kekosongan budaya. Untuk itu, maka bab kedua akan digunakan untuk membahas persoalan kontekstual yang melingkupi proses penciptaan film dari masa ke masa melalui pembahasan mengenai dinamika perfilman itu sendiri di Indonesia. Pembahasan mengenai dinamika perfilman memperlihatkan bagaimana kultur perfilman Indonesia didominasi oleh beragam kepentingan sehingga secara tak langsung berdampak terhadap posisi dan peran perempuan dalam film. Bab ketiga diperuntukkan untuk membahas keterlibatan perempuan secara historis dalam perfilman Indonesia periode kolonial yang membawa serta posisi dan peran mereka sejak awal perfilman Indonesia mulai dibangun, sementara pada bab keempat akan digunakan untuk membahas keterlibatan perempuan yang mulai mengalami pergeseran dari dalam layar ke balik layar pasca kemerdekaan. Hal ini dilakukan untuk melihat bagaimana transformasi peran perempuan dalam industri perfilman di indonesia pasca kemerdekaan. Mengenai siapa saja mereka, apa saja yang melatari serta hambatan yang ditemuinya juga akan dideskripsikan di dalam bab ini. 26 Beragam respon masyarakat terkait penampilan dan perilaku para aktris pada masanya juga akan dipaparkan pada subbab terakhir bab empat.35 Mengingat bagaimanapun bentuk kemajuan yang diperoleh perempuan dalam perfilman Indonesia akan selalu berlangsung bertahap, sementara perempuan dalam perfilman Indonesia menghadapi beragam ketidakadilan gender untuk bersaing dalam industri perfilman, kehadiran mereka rupanya masih terus dihakimi dan dihormati atas dasar penampilan atau fisik semata. Dengan begitu, diketahui bahwa masyarakat tidak berlaku pasif terhadap penampilan dan perilaku para aktris, sebaliknya masyarakat juga ikut berperan dalam mengontrol penampilan dan perilaku mereka sepanjang periode tersebut. Bab kelima merupakan bab yang selain menyimpulkan hasil dari penelitian ini juga menjawab inti permasalahan yang telah disampaikan pada bab terdahulu. 35 Hal ini akan sangat berkaitan dengan pemahaman akan fungsi film sebagai sarana kontrol sosial yang potensial dimana film juga mempunyai kecenderungan untuk mempromosikan nilai konformitas, mulai dari gaya rambut, berpakaian, perbendaharaan kata atau jargon, bahkan juga sikap dan pandangan tertentu dengan cara yang lebih halus. Budi K. Zaman, Laporan Penelitian Bahasa Film: Teks dan Ideologi (FISIPOL UGM: Yogyakarta, 1993), hlm. 6668. 27