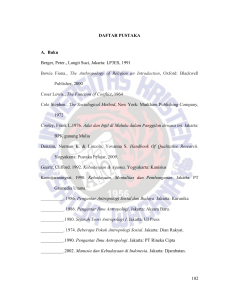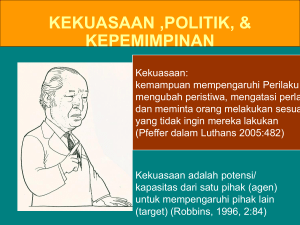PENGHAMPIRAN ANTROPOLOGI ATAS
advertisement

Jurnal Antropologi Sosial Budaya ETNOVISI • Vol. 1 • No.3 • Desember 2005 PENGHAMPIRAN ANTROPOLOGI ATAS KEBIJAKAN DAN KEKUASAN (Berefleksi dari kebijakan Otonomi Daerah) Fikarwin Zuska Departemen Antropologi Fisip USU Abstract This article discusses how Anthropology sees changes in centralized political system to decentralized power. These alternation lead to policy changes that involve the actors as decision makers and people as a target of policy implementation. One of the most significant in policies is how it work smoothly as the wishes of the people. How anthropology deals with such issues by seeing policy as language and cultural agent will be explained in this article. Keywords: regional autonomy, centralization, and resistance Pengantar Kebijakan Otonomi Daerah ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Isi pokok dari kebijakan ini adalah “diperbesarnya kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Dalam ilmu politik kebijakan ini dianggap sebagai tindakan mengubah sistem pemerintahan negara RI dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi 71 . Perubahan sistem pemerintahan ini, di satu pihak, dituliskan dalam berbagai dokumen resmi (aturan perundang-undangan 72 ) atau dalam tulisan-tulisan para pejabat dan pakar, serta berulang-ulang diucapkan lewat kata-kata dalam berbagai pidato pejabat dan elite politik. Dibahas berulangkali dalam berbagai kelas kuliah dan kelompok diskusi di seluruh tanah air, diulas dalam artikel di berbagai media cetak, buku, dan situs internet, talk show interaktif di pelbagai stasiun televisi, percakapan interaktif di pelbagai radio serta di beberapa mailist groups dan atau dengan cara-cara lain yang melibatkan warga masyarakat, anggota partai politik, universitas, lembaga-lembaga non-pemerintah (domestik dan asing), dan masih banyak yang lainnya dengan menghabiskan dana, tenaga, dan waktu yang tak terhitung banyaknya, hingga sekarang dan entah masih sampai kapan akan berhenti. Di lain pihak, pelaksanaan kebijakan otonomi daerah ini ditandai pula dengan perubahan-perubahan dalam struktur organisasi pemerintah (eksekutif) di daerah-daerah 73 , serta hubungan-hubungan di antara pemerintah dan legislatif (DPRD), 74 pemerintah dan 71 73 Tiap daerah (kabupaten/kota atau provinsi) mempunyai organisasi pemerintahan sendiri, dan tidak harus seragam satu dengan yang lain unsur-unsur komponensialnya kecuali (hingga saat ini) pada unsur-unsur: (1) adanya jabatan-jabatan bupati/ wakil bupati dan sekretaris daerah, wali kota/ wakil wali kota dan sekretaris daerah, gubernur/ wakil gubernur dan sekretaris daerah; (2) bupati/wakil bupati, wali kota/ wakil wali kota, gubernur/ wakil gubernur merupakan jabatan politik, sedangkan sekretaris daerah merupakan jabatan karier (pegawai negeri sipil) setara eselon I; (3) bupati, wali kota dan gubernur mempunyai kedudukan sederajat ─hal yang membuat lahirnya asosiasi-asosiasi ‘baru’ yang saling bersaing hingga sekarang, yaitu APKASI, APEKSI dan APPSI. 74 De facto DPRD (terdiri dari politisi partai-partai politik Sistem sentralisasi adalah sistem di mana semua urusan yang ditetapkan dalam konstitusi sebagai urusan negara akan menjadi urusan pemerintah pusat. Dan apabila pemerintah lokal diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangga sendiri (dengan urusan dan sumber keuangan sendiri) sesuai dengan karakteristik daerahnya maka negara itu menerapkan sistem desentralisasi. Lihat Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992) hal. 191. 72 Suatu teks tertulis yang dikeluarkan oleh lembagalembaga kenegaraan (resmi), dengan format dan gaya bahasa tertentu (baku), penuh dengan pasal-pasal berupa ketentuan-ketentuan, dan biasanya juga menyebut ‘keberlakuan’ nya bagi: Apa, Siapa, Kapan, Di mana, Bagaimana dan Mengapa. 151 Fikarwin Zuska Penghampiran Antropologi Atas Kebijakan dna Kekuasaan … masyarakat, 75 serta perubahan-perubahan yang berkenaan dengan wilayah teritori sesuatu daerah, juga hak dan tanggungjawab atas sumberdaya yang ada di wilayah itu, 76 dan masih banyak yang lainnya. Lahirnya peraturan daerah–peraturan daerah (Perda) yang semakin sering dan semakin banyak di sesuatu daerah adalah juga pertanda bahwa kebijakan OTDA mempunyai dampak kepada daerah. Faktanya pemerintahan kabupaten/kota (pemerintah dan DPRD) semakin giat membuat kebijakankebijakan lokal atau regulasi-regulasi baru bagi daerahnya. 77 Setiap kebijakan yang dibuat, sedikit atau banyak, pasti berdampak bagi kehidupan masyarakat di daerah itu atau bahkan lebih luas lagi 78 . Melihat dua deskripsi yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan Otonomi Daerah, seperti tertuang dalam dua alinea di atas, terpikir oleh saya untuk juga mengatakan otonomi daerah sebagai ‘objek pembicaraan’ atau ‘buah bibir’ yang menggairahkan sebagian anggota masyarakat untuk ikut serta. Tetapi kalau saya tahu bahwa besarnya gairah dan banyaknya kini orang-orang terlibat membicarakan sesuatu kebijakan pemerintah, bahkan dengan terangterangan mengkritik kebijakan itu, saya pun pemenang pemilu) cukup berpengaruh atas pemerintah dibanding sebelum OTDA. Nuansa kebijakan partai politik mayoritas/terbesar di tiap-tiap Dewan dan komposisi anggota Dewan berdasarkan partai, ikut mewarnai jalannya proses pemerintahan serta pemilihan kepala daerah, termasuk peluang melakukan money politics. 75 Masyarakat dapat berarti warga negara, tetapi bisa juga warga kelompok-kelompok penduduk setempat (etnis, daerah, agama, dan afiliasi lain-lain), serta NGO’s ikut mengontrol jalannya pemerintahan. Bahkan ada yang aktif menjadi ‘tim sukses’ pencalonan dan atau ‘tim pengganjal’ calon bupati atau gubernur. Isu “putra daerah” merupakan komoditi yang laku dijual dalam kampanye pemilihan kepala daerah. 76 Pemekaran daerah banyak terjadi setelah OTDA, dan hal itu diikuti oleh pembagian wilayah berikut hak dan tanggung jawab atas sumberdaya-sumberdaya yang terkandung di dalamnya. Contoh sederhana adalah air, air sungai dan air bawah tanah, beserta sarana dan prasarananya: siapa berahak mengatur (termasuk memungut retribusi) dan mengurusnya? 77 Harian Kompas: Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi isu sentral di dalam masalah ini. Lihat juga Emil Salim, Seranah Kekuasaan dalam Hery Susanto dkk. (ed), Otonomi Daerah dan Kompetensi Lokal: Pikiran Serta Konsepsi Syaukani HR (Jakarta: Millenium 2003) hal.ixxix 78 Contoh kecil: penutupan TPA-Bantar Gebang oleh Pemerintah Kota Bekasi, merepotkan Pemda DKI mencari tempat murah pembuangan sampah akhir. 152 rasanya ingin mengatakan bahwa kebijakan otonomi daerah adalah sebuah tanda di mana rakyat mulai berani dan pemerintah pun mulai bisa menerima penolakan-penolakan dari rakyat. Apakah itu berarti otonomi daerah merupakan bagian dari demokratisasi? Atau ‘roh halus’ yang menggerogoti batas-batas, laranganlarangan, pantangan-pantangan, tabu-tabu, yang dulu sempat dibuat sebagai diskursus untuk menopang, menyokong, dan melindungi bangunan otoritarianisme Orde Baru? Tulisan ini belum akan menjawab semua pertanyaan itu sebelum ada data dan bukti-bukti dari lapangan yang bisa disusun jalin menjadi argumentasi. Makalah ini hanya akan membuat rintisan (jalan) agar pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan fenomena otonomi daerah tadi bisa dijelaskan secara antropologis, yaitu meletakkan perkara otonomi daerah dalam konstelasi perteorian antropologi: apa kebijakan (policy) menurut teori-teori antropologi sementara ini? Bagaimana antropologi memandang suatu kebijakan? Kebijakan dan Antropologi Seperti diketahui selama ini, studi kebijakan kebanyakan menerima input dari ilmu politik, administrasi publik, kebijakan sosial, kajian organisasi, hubungan internasional dan sebagainya. 79 Antropologi sendiri baru belakangan ini diakui oleh banyak penulis memberi input terhadap kajian kebijakan. 80 Selama ini, walaupun de facto antropologi kebijakan telah ada, tapi identitasnya sebagai antropologi kebijakan tidak begitu jelas (lacking a clear identity); malahan sering disebut dengan sesuatu yang lain, atau tidak langsung disebut dengan antropologi kebijakan. 81 Kebijakan (policy) yang kini telah menjadi bahan kajian antropologi sudah semakin luas batas dan pengertiannya. Kebijakan (policy) itu 79 William N. Dunn, Pengatar Analisis Kebijakan Publik (edisi kedua) (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 1994). 80 Cris Shore & Susan Wright, “Preface and Acknowlegements”, dalam Cris Shore & Susan Wright (ed), Anthropology of Policy: Critical Perspectives On Governance and Power (London & New York: Routledge 1997) hal. xiii. 81 Cris Shore & Susan Wright, “Policy: A New field of anthropology”, dalam Cris Shore & Susan Wright (ed), Anthropology of Policy: Critical Perspectives On Governance and Power (London & New York: Routledge 1997) hal. 6. Jurnal Antropologi Sosial Budaya ETNOVISI • Vol. 1 • No.3 • Desember 2005 kini telah menjadi konsep dan instrumen yang semakin sentral dalam organisasi masyarakat kontemporer. Kebijakan itu telah menyentuh semua gelanggang kehidupan (areas of life) di negara-negara modern sehingga betul-betul mustahil bagi kita untuk menghindar atau melepaskan diri dari pengaruhnya. Bahkan lebih dari pada itu, bahwa kebijakan juga sudah semakin menentukan cara individu-individu mengkonstruksikan dirinya sendiri sebagai seorang pelaku (subject). Melalui kebijakan, individu dikategorisasi dan diberikan status serta peranan-peranan seperti ‘subject’, ‘citizen’, ‘profesional’, ‘national’, ‘criminal’, dan ‘deviant’. “Dari buaian hingga liang lahat orang diklasifikasi, dibentuk, dan ditata menurut kebijakan, tetapi orang itu hanya menemukan sedikit kesadaran tentang, atau kontrol atas, bekerjanya proses-proses itu”. Itulah sebabnya, kata Shore & Wright, studi tentang kebijakan ini, dapat langsung memasuki isu-isu yang terletak di jantung antropologi. Shore & Wright (1997:4) juga mengatakan secara tidak langsung bahwa masuknya praktikpraktik dan gagasan-gagasan pemerintahan neoliberal dari Eropa dan Amerika Utara ke negara-negara Selatan, pun berkaitan erat dengan penggunaan kebijakan sebagai instrumen kekuasaan untuk membentuk individu-individu, atau sebagai political technology (istilah ini dikutip oleh Shore dan Wright dari Faucoult). Dihubungkan dengan “a more global phenomenon of changing patterns of governance”, Shore & Wright mengatakan bahwa gagasan dan praktik pemerintahan neoliberal yang ada sekarang di luar Eropa dan Amerika Utara, ini pun diekspor ke Selatan melalui ‘international structural adjustment programmes and Western training schemes” yang diikuti oleh para pembuat kebijakan (policy makers) dari Selatan (dunia ketiga). Tetapi antropologi dapat memberi pemahaman pada kebijakan yang bekerja pada strukturstruktur baru itu, dan pada kebijakan yang diartikulasikan lewat diskursus-diskursus dan perwakilan-perwakilan itu. Dengan mempelajari kebijakan itu, kata Shore dan Wright, kita dapat menerangkan perubahan gaya dan sistem pemerintah dan bagaimana perubahan itu mengkonfigurasikan kembali hubungan antara individu dan masyarakat. Pengkajian tentang kebijakan ini, sebagaimana tersebut dalam karya Shore & Wright (1997:5) telah mengalami kemajuan sejak pengkajian-pengkajian antropologi mengenai organisasi menemukan kenyataan bahwa: (1) “Organizations exist in a constant state of organizing, and that process revolves around the concept of policy”. Kebijakan itu, dalam organisasi-organisasi besar, makin lama makin tersusun secara sistematis, terpublikasi (publicized) dan diacu oleh para pekerja dan para menejer sebagai pedoman yang sah dan memotivasi perilaku mereka. Sambil meminjam metafor dari Arthur Koestler, Shore & Wright (1997:5) mengatakan bahwa kebijakan itu adalah seperti ‘the ghost in mechine’─kekuatan yang meniupkan kehidupan dan tujuan ke dalam mesin pemerintahan dan menghidupkan tangan yang sudah mati dari suatu birokrasi. Kapasitas ini menstimulasi dan menyalurkan aktivitas yang sebagian besar berasal dari “the objectification of policy”─proses untuk menjadikan kebijakan-kebijakan mendapatkan legitimasi dan eksistensi yang benar-benar nyata; (2) Policy fragments (fragmentasifragmentasi kebijakan)─yang mengandung arti bahwa suatu kebijakan bisa sangat berbeda-beda dalam berbagai macam rupa manifestasinya. Maka dari itu proses pengorganisasian adalah sebenarnya merupakan kerja “mengusahakan manifestasi-manifestasi yang terfragmentasi” itu agar tampak bertalian secara logis/ masuk akal (coherent) sehingga ia dapat dikatakan sebagai wujud atau hasil pencapaian yang sukses dari suatu maksud atau tujuan (intention) 82 . Kaum instrumentalis bahkan mengkonseptualisasikan kebijakan sebagai “alat untuk mengatur penduduk dari atas ke bawah, melalui penghargaan-penghargaan dan sanksisanksi. Kebijakan, menurut pandangan ini, sama sekali merupakan instrumen yang secara intrinsik bersifat teknis, rasional, dan actionoriented; ia (kebijakan) itu dipakai oleh para pembuat keputusan (decision makers) untuk memecahkan masalah-masalah dan untuk mempengaruhi perubahan. Oleh sebab itu, secara singkat dapat dikatakan, bahwa kebijakan (policy) memang telah menjadi sebuah institusi pokok dari pemerintah terutama di Barat dan internasional; konsep kebijakan itu telah berada dalam tingkat yang sama kedudukannya dengan konsep-konsep pengorganisasian yang sudah sejak lama ditekuni dalam ilmu sosial, yaitu 82 Ibid hal,5. 153 Fikarwin Zuska Penghampiran Antropologi Atas Kebijakan dna Kekuasaan … ‘family’ dan ‘society’. Itulah pula sebabnya sekarang kebijakan (policy) dapat dipandang sebagai fenomena antropologis, yang bisa dibaca oleh ahli antropologi dalam bermacam cara: “As cultural texts, as classificatory devices with various meanings, as narratives that serve to justify or condemn the present, or as rhetorical devices and discursive formations that function to empower some people and silence others. Not only do policies codify social norms and values, and articulate fundamental organizing principles of society, they also contain implicit (and sometime explicit) models of society”. 83 Shore & Wright (1997) lebih lanjut mengatakan bahwa ahli antropologi bisa melihat kebijakan sebagaimana gagasan Malinowski tentang ‘mitos’ dalam masyarakat Trobriand, yang disebutnya berperan sebagai ‘a guide to behaviour and charter for action’; atau seperti dikatakan Buckley sebagai ‘a rhetorical commentary that either justifies or condemns; as a charter for action; and as a focus for allegiance.” Bahkan kebijakan dapat dipelajari seperti konsep ‘total social phenomena’ nya Marcuss karena implikasinya yang penting dalam ekonomi, hukum, budaya dan moral serta kemampuannya yang dapat menciptakan seperangkat hubungan antara individu-individu, kelompok-kelompok dan objek-objek. Juga seperti ‘dominant symbol’ nya Turner atau ‘core symbol’ nya Schneider, dan lain sebagainya. Shore & Wright (1997) sendiri mengelompokkan tiga pendekatan yang bisa dan telah dipergunakan dalam menganalisis kebijakan. Ketiga pendekatan itu ialah pendekatan yang melihat kebijakan sebagai languange, sebagai cultural agent dan sebagai political technology. Dalam hal yang pertama, dipelajari bahasa dan diskursus kebijakan; perhatian dipusatkan pada ‘rhetorical devices’ yang biasa digunakan oleh para politisi untuk mempengaruhi dan mengontrol audiens. Selain itu, dimensi esensialnya, yakni analisis tentang dokumen-dokumen kebijakan tertulis. Dalam kajian tersebut, konsep diskursus menjadi penting. Shore & Wright mendefiniskan diskursus sebagai konfigurasi-konfigurasi dari gagasan-gagasan yang dijalin untuk membangun 83 Ibid hal.7. 154 ideologi. Bahasa, dalam definisi ini, dipahami bukan sebagai sebuah bidang yang otonom, melainkan dibentuk secara sosial (socially constituted), dan ketertarikan antropologi pada diskursus ini justru pada apa yang disebut dengan ‘politik praktika diskursif’. Intinya adalah siapakah yang berkuasa mendefinisikan diskursus-diskursus dominan yang bekerja dengan menyusun terms of reference dan menolak atau memarjinalkan alternatif-alternatif lain. Kebijakan memungkinkan hal ini terjadi dengan merancang sebuah agenda politik dan memberikan otoritas institusional kepada satu atau sejumlah diskurus. Dalam proses pembentukan suatu diskursus baru, ‘kata-kata kunci’ tertentu mengalami perubahan arti dan kegunaan. Sebagai contoh adalah kebudayaan, yang cukup lama diasosiasikan dengan cultivation, maka pada abad ke-18 berubah menjadi satu istilah yang di dalam pengertiannya terkandung juga ‘art’, ‘civilizations’, ‘development’, ‘science’, dan ‘community’. Ini terjadi bersama dengan lahirnya kekuasaan modern (the birth of modern power). Jadi perubahan semantik tersebut memberi ‘sidik jari’ untuk menelusuri transformasi yang lebih besar dalam rasionalitas pemerintah. Kebijakan sebagai cultural agent dipahami dengan cara bahwa pemerintah memainkan peranan penting dalam mengonstruksikan identitas nasional. Seluruh penduduk dapat dikonstruksikan seperti warga negara baru dan subjek kekuasaan dengan cara-cara yang tak sepenuhnya mereka sadari. Bahkan, pemerintah sengaja menyamarkan kebijakannya itu sedemikian rupa sehingga seoalah-olah hal itu merupakan inisiatif otentik warga. Persis seperti dikatakan Foucult, bahwa keefektifan kekuasaan justru terletak pada kemampuan untuk menutupi kekuasaan dan menyamarkan mekanismenya. Dalam kasus pembentukan identitas Kanada, misalnya, novel dan film digunakan sebagai alat untuk pengintegrasian Eropa Bersatu dengan jalan memperkuat semangat kompetitif Eropa dan memajukan nilai-nilai Eropa serta kebudayaan Eropa untuk menghadapi imperialisme budaya Amerika dan Jepang. Selanjutnya kebijakan sebagai teknologi politik, yaitu kebijakan dipahami lebih sebagai suatu bentuk kekuasaan yang bekerja atas pemahaman diri sendiri individu. Consern pendekatan ini pada umumnya adalah Jurnal Antropologi Sosial Budaya ETNOVISI • Vol. 1 • No.3 • Desember 2005 menganalisis proses-proses pengadopsian dan penginternalisasian norma-norma bertindak yang baru oleh para individu. Dalam hal ini fokus perhatian ditujukan pada bagaimana ‘techniques of the self’ bekerja melahirkan subjek-subjek kekuasaan baru. Analisis Foucault tentang hubungan antara power, normalisasi, dan subjektivitas, menjadi acuan dalam hal ini. Terutama analisisnya mengenai rasionalitas pemerintah; analisis yang dianggap sebagai startring point untuk memahami bagaimana sistem-sistem kekuasaan modern bekerja. Dia mengatakan bahwa perubahan besar telah terjadi dalam rasionalitas pemerintah pada pertengahan abad ke-18, yaitu dalam konseptualisasi mengenai ruang yang diperintah dan tentang pemerintahan itu sendiri. Pada era pramodern, pemerintah berusaha menjaga kedaulatan atas suatu teritori, maka pada 1840-an ‘populasi’ mengganti prinsipalitas (kerajaan) sebagai objek pokok pemerintahan. Kelahiran era modern, menurut Foucault, ditandai oleh permulaan suatu sistem kekuasaan baru di mana ‘problem of population’ (kesehatannya, kesejahteraan, kesuburan, edukasi, kelakuan moral) dan kontrol atas tubuh manusia menjadi ‘central foci’ dari pengawasan dan penertiban negara’. Rasionalitas pemerintahan liberal modern adalah ‘the art of applying’ prinsip-prinsip ekonomi pada pengelolaan populasi. Jadi, pertanyaan dari pemerintahan modern itu adalah bagaimana mengintroduksikan ekonomi, yaitu cara benar mengelola individu, barang dan kesejahteraan dalam keluarga, ke dalam pengelolaan negara. Perubahan rasionalitas pemerintahan ini dapat dilihat paling nyata dalam teknologi politik, yaitu kebijakan. Kekuasaan, Kebijakan, dan Resistensi Dari pendefinisian dan pendekatan yang dikemukakan oleh Shore & Wright di atas, tampak suatu hal penting telah terjadi bahwa kebijakan (policy) itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari pada isu kekuasaan (Hansen 1999:89). Dalam hal ini kebijakan dapat diartikan dengan cara bagaimana pemerintah memainkan kekuasaan melalui kebijakankebijakan. Tetapi kekuasaan di sini harus dipahami dengan cara nonkonvensional, atau sebagaimana hal itu misalnya dimaklumkan oleh Angela Cheater dalam tulisannya “Power in The Postmodern Era”. Pemahaman akan power dalam era postmodern ini, kata Cheater, berbeda jauh dari faham pengikut-pengikut Weber yang mengadakan pemisahan antara kekuasaan (as the ability to elicit compliance) dan otoritas (as the right to expect compliance). Dan perubahan itu─kata dia lagi─banyak bergantung pada Michael Foucault dan postmodernisme, serta kemungkinan semakin melemahnya otoritas negara atas organisasi-organisasi global dan subnasional yang terus menghilang (Cheater 1999:2). Foucault memisahkan antara ‘central regulated and legitimate forms of power’ dan ‘capillary power at extremities’. Pembagian ini bisa barangkali disejajarkan dengan pembagian Blau dan Scott mengenai formal organization dan informal relationship, atau dari Skalnik yang mengatakan power berasal dari negara sedangkan otoritas berakar pada popular approval (persetujuan khalayak). Tetapi bagi Foucault sendiri, seperti dikutip Cheater (1999:3), tampaknya tidak membedakan power dan otoritas karena individu-individu biasa pun melaksanakan kekuasaan. “Individuals… are always in the position of simultaneously undergoing and exercising this power. They are not only its inert or consenting target; they are always also the elements of its articulation……the vehicles of power, not its points of application”. Jadi kekuasaan, menurut pengertian itu, tidak semata-mata dimainkan oleh negara (state) saja melainkan juga dimainkan oleh para individu. Demikian bila kebijakan (policy) dikaitkan dengan kalimat “Dari buaian hingga liang lahat, orang diklasifikasi, dibentuk, dan ditata menurut kebijakan, tetapi orang itu hanya menemukan sedikit kesadaran tentang, atau kontrol atas, bekerjanya proses-proses itu,” bukanlah berarti hal itu akan terjadi secara sertamerta. Para individu, yang diharapkan menjadi target dari kebijakan itu, niscaya akan mengadakan ‘perlawanan-perlawanan’ (resistence) dengan atau melalui kekuasaankekuasaan yang bisa dimainkannya. Itulah sebabnya Abu-Lughod (1989)─sambil mengutip Foucault yang berkata ‘where there is power, there is recistance’─bisa mengatakan bahwa resistensi itu adalah sebagai diagnostik kekuasaan (a diagnostic of power). Dan kekuasaan itu, tidak seperti pemahaman di abad 20-an, selalu berkonotasi represif atau negatif ─menyangkal, menolak, melarang, atau menekan─tetapi juga bermakna positif: menghasilkan bentuk-bentuk kesenangan, 155 Fikarwin Zuska Penghampiran Antropologi Atas Kebijakan dna Kekuasaan … sistem-sistem pengetahuan, barang-barang, dan wacana-wacana. Kekuasaan, menurut pandangan Foucault, tidaklah dimiliki (possessed) melainkan bermain/dimainkan terus-menerus: “…power is not something which can be possessed by individuals or social groups. Rather, it must be seen as something constantly in play. Power relations, such as those between employers and employees, or between mothers and doctors, are always susceptible to reversal….. Foucault does not limit the sphere of power relations to interactions between the individuals and state apparatuses: they extend throughout the social field, operating between men and women, professionals and their client “(Patton 1987:234). Sehingga kebijakan yang selalu dikaitkan dengan pemerintah itu (instrument of governance) boleh dibilang sebagai alat atau instrumen, yang dipakai pemerintah dalam memainkan kekuasaan yang terdapat di dalam relasi-relasi antara pemerintah dan individuindividu. Namun, sebaliknya juga, para individu pun dapat memainkan kekuasaan untuk mempengaruhi (kalau sanggup) kebijakankebijakan pemerintah. Yang penting di sini adalah apa yang Foucault advokasikan: ‘teknik dan taktik dominasi’ (Cheater 1999:3). Praktiknya, boleh jadi, seperti dikemukakan Scott dengan cara bisu (not voicing) atau voice under domination, termasuk di dalmnya rumor, gosip, samaran-samaran, linguistic trict, metafor, eupimisme, folktale, dan lain-lain (Cheater 1999:5). Semua yang disebut sebagai cara individu memainkan kekuasan di atas, dapat dicakup dalam apa yang disebut dengan diskursus, karena paling tidak, suara-suara itu tidak lagi dipahami hanya sebagai alat atau medium ‘netral’ untuk mengungkapkan kenyataan. Melainkan, di dalamnya, termuat sesuatu yang disebut dengan kekuasaan. Jadi diskursus, dalam hal ini, memegang peranan penting. Di dalam diskursus-diskursus kebenaran atau pengetahuan (discourses of truth or knowledge), ada kekuasaan abadi, bahkan kekuasaan itu terciptakan di sana. “…power is vested, even created, in discourses of truth or knowledge…” 84 Diskursus itu sendiri, oleh 84 Cheater (1999:) menyebut Foucault tidak selalu konsisten dengan gagasan-gagasannya. Kutipan terakhir ini 156 Foucault─seperti dikatakan Patton (1987:230)─skopnya dibatasi hanya pada ‘statements’ yang terjadi dalam institutional and discursive frameworks yang membedakan (mark off) klaim-klaim kebenaran sesungguhnya dari ucapan-ucapan sehari-hari. Hikam (1996:85)─juga mengacu pada Foucault─mengatakan adanya kuasa dalam setiap proses wacana, dan kuasa itu memberikan batasan-batasan tetang apa yang diperkenankan menjadi wacana, perspektif yang mesti dipakai di dalamnya, topik apa yang dibicarakan, dan norma-norma serta elaborasi konsep-konsep dan teori apa yang bisa dan sah untuk dipakai. Tetapi menurut Alam (1998:6)─yang juga mengacu pada Foucault─bahwa wacana (discourse) itu adalah ‘bentuk penuturan verbal yang berkaitan erat dengan kepentingan si penutur, sehingga dapat merupakan suatu akumulasi konsep ideologis yang didukung oleh tradisi, kekuasaan, lembaga, dan berbagai macam modus penyebaran pengetahuan’. Alam (1999:7-8) makin mempertegas keyakinannya bahwa Foucault memahamkan wacana sebagai modus komunikasi verbal yang mengandung ‘kepentingan’ dan ‘kekuasaan’. Sementara kekuasaan tersebut, lanjut Alam, dipahami sebagai kemampuan untuk menstruktur tindakan orang lain dalam bidang tertentu. 85 Kekuasaan yang demikian ini senantiasa beredar dari subjek yang satu ke yang lain. Sementara Shore & Wright (1997:18) mendefinisikan wacana sebagai konfigurasi-konfigurasi dari gagasangagasan yang menyediakan bahan rajutan untuk dirajut menjadi ideologi. Pendefinisian mengenai diskursus ini, meskipun tampak berbeda, tetapi semuanya mengisyaratkan adanya ‘tenaga’ 86 atau adalah salah satu contoh betapa Foucault seolah-olah melupakan deskripsi-deskripsi sebelumnya tentang kekuasan, seperti misalnya ia mengatakan bahwa power tidak terberikan (given), tidak dipertukarkan, dan juga tidak terpulihkan, melainkan dilaksanakan dalam tindakan. 85 Bandingkan dengan keterangan Wolf (1994:) atas konsep kekuasaan Foucault. Wolf mengatakan gagasan Michael Foucault’s tentang power adalah “…as ability to structure the possible field of action of others’. Itu sebabnya Wolf menggolongkan pemahaman Foucault atas power ini ke dalam moda ‘structural power’ dan berbeda dari apa kata Wolf dengan moda “tactical or organizational power”, dan ‘power as the attribute of persons’ serta ‘power as ability of ego to impose its will on an alter in social action, in interpersonal relations’ 86 Wolf (1994:219) jelas-jelas menyebut apa yang oleh Foucault disebut dan diartikan dengan power itu, adalah Jurnal Antropologi Sosial Budaya ETNOVISI • Vol. 1 • No.3 • Desember 2005 ‘kekuatan’ yang mengalir dalam diskursus sehingga boleh jadi ia akan ‘membelokkan’ atau bahkan ‘menyingkirkan’ apa yang tadi kita namakan ‘kebijakan’ pemerintah. Itulah kekuasan yang individu-individu mainkan atau salurkan lewat diskursus sebagai satu bentuk resistensinya dalam menghadapi kekuasaan yang dimainkan pemerintah melalui kebijakankebijakannya atau wacana-wacananya. AbuLughod (1989), misalnya, walaupun bukan dalam konteks hubungan antara pemerintah dan individu-individu (warga negara), telah menangkap ‘resistensi’ demikian itu dalam konteks hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dalam komunitas orang Bedouin yang tersegregasi secara seksual, dan menggolongkannya dalam empat tipe, di antaranya adalah dalam bentuk: sexually irreverent discourse. Dalam hal ini wanita, melalui penceritaan cerita-cerita tertentu di antara sesamanya, menertawakan laki-laki dan kelelakian walaupun ideologi resmi memuja hal itu dan wanita pun menghormati, menutupi dan kadang-kadang menakutinya. “Women seem only too glad when men fail to live up to the ideals of autonomy and manhood, the ideals on which their alleged moral superiority and social precedence are based, especially if they fail as a result of sexual desire.” Ini satu bentuk resistensi atau kekuasan yang dimainkan, yang pada gilirannya, bukan tidak mungkin akan dapat menyingkirkan atau menyaingi wacana yang mendominasi (forms of men’s power). Penghampiran teoritis yang membuat individu tampak tidak pasif belaka di hadapan sistem-sistem atau struktur-struktur dominan yang mempengaruhinya ini, selain diskursus, juga ada konsep praksis dari Pierre Bourdieu. Bachtiar Alam (1998:4-5) menyebutkan hal itu karena konsep praksis ini menekankan adanya hubungan timbalbalik antara si pelaku dan apa yang oleh Bourdieu disebut struktur objektif. Hubungan timbal-balik antara pelaku dan struktur objektif itu digambarkan seperti berikut: (1) struktur obyektif direproduksi secara terus menerus dalam praksis para pelakunya yang berada dalam kondisi historis tertentu; (2) dalam proses tersebut para pelaku mengartikulasikan dan mengapropriasi simbolberakar pada Marx. Sedangkan menurut Marx, kata Wolf, bahwa power itu juga bekerja dalam ‘penspesifikasian distribusi dan arah dari aliran-aliran energi’. Tidak hanya dalam arti ekonomi, energi disini juga dalam arti politik. simbol budaya yang terdapat dalam struktur obyektif sebagai tindakan strategis dalam konteks sosial tertentu; (3) sehingga proses timbal balik secara terus-menerus antara praksis dan struktur objektif dapat menghasilkan baik perubahan maupun kontinuitas. Konsep praksis ini sepertinya memberi kepada para pelaku peran untuk sedikit lebih radikal menghadapi struktur-struktur objektif. Oleh sebab itu, untuk masa di mana tawarantawaran dan alternatif-alternatif makin banyak seiring dengan proses globalisasi, konsep praksis ini makin bertambah penting. Dengan cara ini kita bisa pelajari bagaimana proses dan dinamika orang mengkonstruksi dan merekonstruksi budaya 87 yang sesuai dengan kepentingannya. Hal ini sangat boleh jadi akan menegasikan arti dan pengaruh suatu kebijakan yang dikatakan hampir tidak bisa dihindari dalam masyarakat kontemporer. Penutup Tulisan ini dapat diakhiri dengan suatu catatan yang barangkali bisa membuka ruang pengkajian lebih dalam terhadap kebijakan. Sebagai instrumen kekuasaan, kebijakan berpotensi mengkonstruksikan individu-individu ke dalam sistematika atau skenario yang terbawa dalam dirinya. Sejauhmana itu berhasil, tentu diperlukan penyelidikan lapangan yang lebih saksama. Namun keberjarakan antara kebijakan dengan individuindividu selalu terjadi sehingga dimungkinkan pula terjadinya dialektika atau bahkan semacam resistensi: voice under domination. Baik dialektika maupun resistensi, tentu saja akan beragam. Dan ini patut menjadi agenda penelitian. Mengenai kebijakan otonomi daerah, setelah tinjauan teoritis ini dilakukan, juga akan mendapat tempat serupa dengan kebijakankebijakan pada umumnya. Ia berpotensi menarik individu-individu ke dalam skenarionya. Tetapi sejauh mana instrumen kekuasan dalam rangka pengorganisasian organisasi negara RI itu bisa bekerja, perlu diadakan penyelidikan. Namun ‘kesibukan-kesibukan’ sebagaimana terdeskripsi 87 Borofsky (1994:318) menambahkan bahwa dengan konstruksi dan rekonstruksi budaya, baik dalam pemulihan kembali (rediscovery) tradisi-tradisi lama maupun dalam formulasi tradisi-tradisi baru, kita melihat the cultural in motion. Dia menjadi alat pemberdayaan (a tool of empowerment, a symbol for unifiying one group against another…….the cultural has become something to fight about). 157 Fikarwin Zuska Penghampiran Antropologi Atas Kebijakan dna Kekuasaan … pada bagian awal tulisan ini, sedikit banyak menunjukkan bahwa ada sebagian orang yang masuk dalam skenario OTDA tetapi pada saat Daftar Pustaka yang sama sebagian orang lagi mengambil ‘kesempatan’ yang mungkin saja berada di luar skenario resmi OTDA. Abu-Lughod, Lila. “The Romance of Resistance: Tracing Transformations of Power through Bedouin Women.” Dalam American Anthropology 17 (1). Hal. 41-55. Alam, Bachtiar. 1999. “Antropologi dan Civil Society: Pendekatan Teori Kebudayaan.” Dalam Antropologi Indonesia Th.XXIII No.60 Sept-Des 1999. Hal.3-10. Alam, Bachtiar. 1997. “Globalisasi dan Perubahan Budaya: Perspektif Teori Kebudayaan.” Dalam Antropologi Indonesia No.54 Th.XXI Des 1997- April 1998. Hal. 1-22. Borofsky, Robert. 1994. ‘The Cultural in Motion.” Dalam Robert Borofsky (ed). Assessing Cultural Anthropology. New York: McGraw-Hill,Inc. Hal. 313-319. Capra, Fitjof. 2001. Jaring-Jaring Kehidupan Visi Baru Epistemologi dan kehidupan. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru. Cheater, Angela. 1999. “Power in The Postmodern Era.”alam Angela Cheater (ed). The Anthropology of Power: Empowerment and Disempowerment in Changing Structure (London & New York: Routledge. Hal. 1-12. Dunn, Wiiliam N. 1994. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Goldschmidt, Walter. (ed). 1986. Anthropology and Public Policy: A Dialogue. A Special Publication of American Anthropological Association No. 21. Hansen, Helle Ploug. 1999. “Patients’ Badies and Discourses of Power.” dalam Chris Shore & Susan Wright (ed). Anthropology of Policy: Critical Perspective on Governace and Power. London & New York: Routledge. Hal. 88-104. Hikam, Muhammad A.S. 1996. “Bahasa dan Politik: Pengahampiran ‘Discursive Practice’.” dalam Yudi Latif & Idi Subandy Ibrahim (ed) Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru. Bandung: Mizan. Hal. 77-93. Patton, Paul. 1987. “Michel Foucault” dalam Diane J. Austin-Bross (ed).Creating Culture. Sydney, London, Boston: Allen & Unwin. Hal. 226-242. Salim, Emil. 2003. “Seranah Kekuasaan.” Dalam Hery Susanto, dkk. (penyusun). Otonomi Daerah dan Kompetensi Lokal: Pikiran serta Konsepsi Syaukani HR. Jakarta: Millenium Publisher. Hal. ix-xix. Shore, Chris & Susan Wrighat. 1997. “Policy A New Field of Anthropology.” Dalam Chris Shore & Susan Wright (ed). Anthropology of Policy: Critical Perspective on Governace and Power. London & New York: Routledge. Hal. 3-39. Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. Wolf, Eric R. 1994. “Facing Power: Old Insights, New Questions.” Dalam Robert Rorofsky (ed). Assessing Cultural Anthropology. New York: McGraw-Hill,Inc. Hal. 218-228. 158