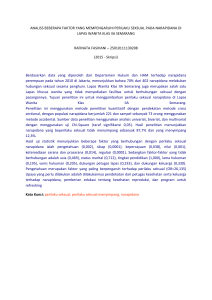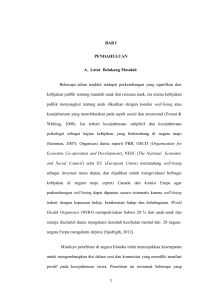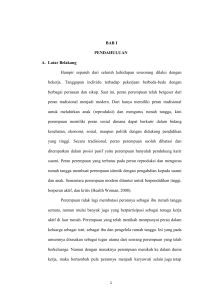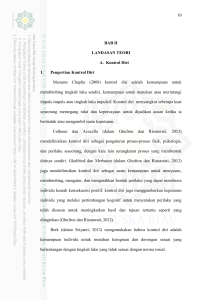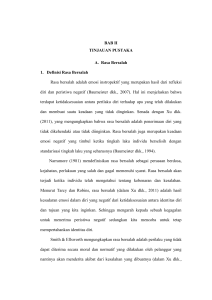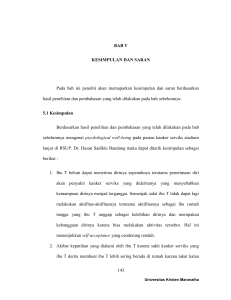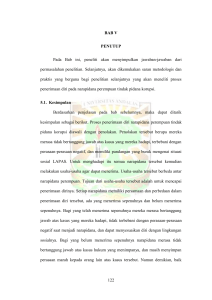BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Psychological Well Being 1
advertisement

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Psychological Well Being 1. Pengertian Psychological Well Being Penelitian mengenai Psycological well-being pertama kali dikembangkan oleh Ryff (Astuti, 2011) yang mengatakan bahwa psycological well-being mulai berkembang sejak para ahli menyadari bahwa selama ini psikologi lebih banyak memberikan perhatian kepada penderitaan atau ketidakbahagiaan seseorang daripada bagaimana seseorang dapat berfungsi secara positif. Psycological well-being merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kesehatan psikologis individu berdasarkan pemenuhan kriteria fungsi psikologi positif (Ryff dalam Astuti, 2011). Ryff (Papalia dkk, 2008) menyebutkan bahwa mental health tidak hanya sebagai ketiadaan mental illness. Positive mental health, termasuk di dalamnya psycological well-being, merupakan perasaan sehat tentang diri sendiri. Sementara Diener (Fransisca, 2009) mengatakan bahwa perasaan well-being atau happiness merupakan evaluasi personal seseorang terhadap hidupnya sendiri. Papalia (2008) menyatakan bahwa orang yang sehat secara psikologis memiliki sikap positif terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Individu dapat membuat keputusan sendiri, dan memilih atau membentuk lingkungan yang sesuai dengan kebutuhannya. Individu memiliki tujuan yang 10 11 membuat hidupanya lebih bermakna, dan berjuang serta mengembangkan diri semaksimal mungkin. Tenggara dkk (2008) menyatakan, kesejahteraan psikologis bukan hanya merupakan ketiadaan penderitaan, namun meliputi keterikatan aktif dalam dunia, memahami arti dan tujuan hidup dan hubungan dengan seseorang pada objek ataupun orang lain. Psycological well-being berakar dari adanya kebutuhan untuk merasa baik secara psikologis (psychologicallywell). Ryff (1989) menambahkan bahwa psycological well-being merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan apa yang dirasakan individu mengenai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari yang mengarah pada pengungkapan perasaan-perasaan pribadi atas apa yang dirasakan oleh individu sebagai hasil dari pengalaman hidupnya. Menurut Ryff (1989) gambaran tentang karakteristik orang yang memiliki kesejahteraan psikologis merujuk pada pandangan Rogers tentang orang yang berfungsi penuh, padangan Maslow tentang aktualisasi diri, pandangan Jung tentang individuasi, konsep Allport tentang kematangan, juga sesuai dengan konsep Erikson dalam menggambarkan individu yang mencapai integrasi dibanding putus asa. Individu dengan psycological well-being adalah individu yang memiliki respon positif terhadap dimensi-dimensi psycological well-being, yaitu merasa puas dengan hidupnya, kondisi emosionalnya positif, mampu melalui pengalaman-pengalaman buruk yang dapat menghasilkan kondisi emosional negatif, memiliki hubungan positif dengan orang lain, mampu menentukan nasibnya sendiri tanpa bergantung orang lain, mengontrol 12 kondisi lingkungan sekitar, memiliki tujuan hidup yang jelas, dan mampu mengembangkan dirinya sendiri (Ryff, 1989). Psycological well-being bukan hanya kepuasan hidup dan keseimbangan antara afek positif dan afek negatif, namun juga melibatkan persepsi terhadap keterlibatan dengan tantangan-tantangan selama hidup (Keyes, Shomotkin & Ryff, 2002). Pada intinya psycological well-being merujuk pada perasaan seseorang mengenai aktifitas hidup sehari-hari. Perasaan ini dapat berkisar dari kondisi mental negatif, misalnya ketidakpuasan hidup, kecemasan, merasan tertekan, rasa percayadiri yang rendah, sering berperilaku agresif, sampai pada kondisi mental positif, seperti realisasi potensi dan aktualisasi diri (Bradbrun dalam Liwarti, 2013). Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa psycological well-being (kesejahteraan psikologis) merupakan evaluasi individu terhadap kondisi psikologis yang ditandai dengan adanya perasaan positif, kepuasan hidup serta tidak menunjukkan adanya gejala-gejala gangguan mental. Lebih dari itu fungsi psikologis yang positif seperti penerimaan diri, relasi sosial yang positif, memiliki tujuan hidup, perkembangan pribadi, penguasaan lingkungan dan otonomi bayak dialami oleh individu dari pada fungsi psikologi negatif. 13 2. Dimensi-dimensi Psychological Well-Being Ryff dkk. (Papalia dkk, 2008) menggunakan berbagai teori mulai dari Erikson sampai Maslow untuk mengembangkan model multidimensi yang mencangkup enam dimensi kenyamanan dari skala self-report untuk melakukan pengukuran tentang psychological well-being. Ke enam dimensi tersebut, diantaranya : a. Penerimaan diri (self-acceptance) Penerimaan diri merupakan ciri sentral dari konsep kesehatan mental dan juga karakteristik dari orang teraktualisasi diri, berfungsi secara optimal dan matang (Ryff,1998). Individu yang memiliki penerimaan dirinya secara keseluruhan baik pada masa kini dan masa lalunya, individu akan memiliki sikap positif terhadap diri sendiri, memahami dan menerima berbagai aspek diri termasuk kualitas baik maupun buruk, dapat mengaktualisasikan diri, berfungsi optimal dan bersikap positif terhadap kehidupan yanng dijalaninya. Sementara individu yang memiliki penerimaan diri negatif akan merasa tidak puas dengan dirinya sendiri, merasa dikecewakan dengan apa yang terjadi di masa lalu, merasa bersalah dengan beberapa kualitas personal, serta ingin sosok berbeda dari dirinya pada saat ini. b. Hubungan positif dengan orang lain (positive relation with other) Hubungan positif yang dimaksud adalah kemampuan menjalin hubungan interpersonal hangat dan saling percaya, saling mengembangkan pribadi satu dengan yang lain, kemampuan untuk mencintai, berempati, 14 memiliki afeksi terhadap orang lain, serta mampu menjalin persahabatan yang mendalam (Ryff, 1989). Individu yang memiliki hubungan positif terhadap sesamanya diharapkan memiliki hubungan yang hangat, memuaskan dan saling percaya dengan orang lain, peduli terhadap kesejahteraan orang lain, mampu berempati, berafeksi dan membina kedekatan dan memahami perlunya “memberi dan menerima” dalam membina hubungan terhadap orang lain. Sebaliknya, individu dengan hubungan negatif dengan orang lain akan merasa terisolasi dan merasa frustasi dalam membina hubungan interpersonal, sulit bersikap hangat, tidak perduli orang lain, dan tidak berkeinginan untuk berkompromi dalam memertahankan hubungan dengan orang lain. c. Otonomi (autonomy) Dimensi-dimensi otonomi meliputi kualitas-kualitas seperti penentuan diri (self-determination), kemandirian, pengendalian perilaku dalam diri, dan peran locus internal dalam mengevaluasi diri (Ryff, 1989). Dengan kata lain dimensi ini melihat kemandirian setiap individu dalam memutuskan dan mengatur perilakunya sendiri yang bebas dari tekanan pihak manapun. Individu yang memiliki otonomi tinggi tercermin dari sejauhmana individu tersebut mampu mengarahkan diri dan bersikap mandiri, memiliki patokan (standar personal) bagi perilakunya, mampu bertahan terhadap tekanan sosial untuk berfikir dan bertindak dengan cara tertentu. Individu 15 dengan otonomi rendah akan sangat memerhatikan dan memertimbangkan harapan dan evaluasi dari orang lain, menggantungkan diri pada orang lain untuk membuat keputusan penting, serta tidak mudah terpengaruh oleh tekanan sosial untuk berfikir dan bertingkah laku dengan cara tertentu (Ryff,1995). d. Penguasaan lingkungan (environment mastery) Penguasaan lingkungan digambarkan dengan kemampuan individu yang mampu memilih atau menciptakan lingkungan yang sesuai dengan kondisinya, berpartisipasi dalam lingkungan di luar dirinya, mengontrol dan memanipulasi lingkungannya yang kompleks, serta kemampuan untuk mengambil keuntungan dan kesempatan di lingkungan individu (Ryff, 1989). Dengan kata lain dimensi ini melihat kemampuan individu dalam menghadapi berbagai kejadian di luar dirinya dan mengaturnya sesuai dengan keadaan dirinya sendiri. Individu memiliki dimensi tinggi dalam penguasaan lingkungan akan tercermin dari sejauhmana individu tersebut mampu mengelola dan mengontrol berbagai aktifitas eksternalnya, mampu memanfaatkan secara efektif setiap kesempatan yang ada, mampu memilih atau menciptakan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai pribadi serta memiliki kompetensi dalam mengelola lingkungan dimana dia berada. Sebaliknya, individu dengan penguasaan rendah terhadap lingkungan akan mengalami kesulitan dalam mengatur situasi sehari-hari, merasa tidak mampu untuk mengubah atau meningkatkan kualitas lingkungan sekitar serta tidak 16 mampu menyadari peluang yang ada di sekelilingnya, dan kurang memiliki kontrol terhadap dunia luar (Ryff,1995). e. Tujuan hidup (purpose in life) Tujuan hidup memiliki pengertian bahwa individu memiliki pemahanan yang jelas akan tujuan dan arah hidupnya, memiliki keyakinan bahwa individu mampu mencapai tujuan dalam hidupnya, dan merasa bahwa pengalaman hidup di masa lampau dan masa sekarang memiliki makna (Ryff, 1995) Individu yang memiliki dimensi tujuan hidup yang tinggi adalah individu yang memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan dan arah hidup, memiliki makna terhadap hidup sekarang dan masa lalu, memiliki keyakinan yang memberikan tujuan hidup dan sasaran hidup. Sebaliknya, individu yang tidak memiliki tujuan dalam hidup akan kurang memahami makna hidup, tidak dapat melihat tujuan dari kehidupan masa lampau, tidak memiliki keyakinan yang dapt memberikan makna dalam hidup serta tidak memunyai harapan atau kepercayaan yang memberi arti pada kehidupan (Ryff, 1995). f. Pertumbuhan pribadi (personal growth) Untuk mencapai fungsi psikologis yang optimal, seseorang perlu memiliki aspek-aspek pertumbuhan pribadi yang baik. Hal ini antara lain untuk melihat dirinya sebagai sesuatu yang terus berkembang, kemampuan untuk melihat dirinya sebagai sesuatu yang terus bertumbuh dan berkembang, terbuka terhadap pengalaman baru, memiliki keinginan 17 untuk merealisasikan potensinya, serta dapat melihat kemajuan dalam diri dan perilakunya dari waktu ke waktu. Individu dengan dimensi pertumbuhan pribadi tinggi dapat tercermin dari sejauhmana seseorang memiliki perasaan akan perkembangan berkelanjutan, terbuka terhadap pengalaman, serta dapat merealisasikan potensinya melalui kegiatan kegiatan yang terus-menerus (Ryff, 1989). Sementara orang dengan tahap pertumbuhan pribadi yang rendah akan mengalami stagnasi, kurang merasa berkembang dari waktu ke waktu, merasa bosan dan tidak tertarik dengan kehidupan, serta merasa tidak mampu untuk membentuk sikap atau perilaku yang baru. Berdasarkan dimensi-dimensi yang diuraikan di atas, maka diambil kesimpulan bahwa psycological well-being memunyai sekumpulan dimensi, yaitu dimensi penerimaan diri, dimensi hubungan positif dengan orang lain, dimensi otonomi, dimensi penguasaan lingkungan, dimensi tujuan hidup, dan dimensi pertumbuhan pribadi. 3. Faktor-Faktor Psychological Well-Being a. Usia Berdasarkan hasil beberapa penelitian yang dilakukan Ryff (1989) Ryff & Keyes (1995), Ryff & Singer (1996), penguasaan lingkungan dan kemandirian menunjukkan peningkatan seiring perbandingan usia (usia 25-39, usia 40-59, usia 60-74), tujuan hidup dan pertumbuhan pribadi secara jelas menunjukkan penurunan seiring bertambahnya usia, skor 18 dimensi penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain secara signifikan bervariasi berdasarkan usia. Perbedaan usia ini terbagi menjadi tiga fase kehidupan dewasa, yakni dewasa muda, dewasa tengah dan dewasa akhir, dimana dewasa tengah memiliki tingkat psycological wellbeing yang lebih tinggi dibandingkan dengan dewasa awal dan dewasa akhir (Papalia, dkk, 2008). b. Jenis kelamin Berdasarkan hasil beberapa penelitian yang dilakukan Ryff (1989), Ryff & Keyes (1995), Ryff & Singer (1996), faktor jenis kelamin menunjukkan adanya perbedaan signifikan pada dimensi hubungan positif dengan orang lain dan dimensi pertumbuhan pribadi. Dari keseluruhan perbandingan usia (usia 25-39, usia 40-59, usia 60-74), wanita menunjukkan psychological well-being lebih positif jika dibandingkan dengan pria. Sejak kecil, stereotype gender telah tertanam dalam diri anak laki-laki digambarkan sebagai sosok agresif dan mandiri, sementara itu perempuan digambarkan sebagai sosok pasif dan tergantung, serta sensitif terhadap perasaan orang lain (Papalia, dkk, 2008). c. Tingkat pendidikan dan pekerjaan Status perkerjaan yang tinggi atau tingginya pendidikan seseorang menunjukkan bahwa individu memiliki faktor pengamanan (uang, ilmu, keahlian) dalam hidupnya untuk menghadapi masalah, tekanan dan tantangan (Ryff & Singer, 1996). Hal ini terkait dengan kesulitan ekonomi, dimana kesulitan ekonomi menyebabkan sulitnya individu untuk 19 memenugi kebutuhan pokoknya sehingga menyebabkan menurunnya kesejahteraan psikologis (Maharani, 2015). d. Status sosial ekonomi Ryff (Maharani, 2015) menyatakan bahwa faktor status sosial ekonomi menjadi sangat penting dalam peningkatan psycological wellbeing. Ryan & Deci (2001) menegaskan, status sosial ekonomi berhubungan dengan dimensi penerimaan diri, tujuan hidup, penguasaan lingkungan, tujuan hidup dan pertumbuhan pribadi. Status sosial ekonomi juga memengaruhi kesejahteraan psikologis, seperti besarnya income keluarga, tingkat pendidikan, keberhasilan pekerjaan, kepemilikan materi dan status sosial di masyarakat (Piquart & Serenson dalam Maharani, 2015). e. Budaya Hasil penelitian Ryff & Singer (Fransisca, 2009) dengan memerhitungkan latar belakang budaya menunjukkan, bahwa secara umum orang Amerika yang cenderung individualistic independent lebih mudah melihat kualitas positif dalam diri mereka dibandingkan dengan orang Korea yang dianggap lebih bersifat kolektivistik. Responden dari Korea Selatan menilai tinggi dimensi hubungan positif dengan orang lain dan menilai diri rendah pada penerimaan dan pertumbuhan diri. Responden Amerika menilai diri tinggi pada pertumbuhan pribadi khususnya pada wanita, dan berbeda dari dugaan semula bahwa ternyata wanita Amerika menilai rendah pada dimensi otonomi. 20 f. Dukungan sosial Menurut Lemme (1995), dukungan sosial umunya dipercaya memiliki efek positif baik pada kesejahteraan fisik maupun kesejahteraan psikologis. Robinson (Rubbyk, 2005) juga menemukan bahwa orangorang yang mendapat dukungan sosial memiliki tingkat psycological wellbeing lebih tinggi. Dukungan sosial dari orang lain sangat berarti dalam hidup, tidak hanya bermanfaat langsung bagi well-being tapi juga penghalang bagi seseorang dari efek peristiwa menyakitkan dalam hidup seperti tidak bekerja, kecelakaan atau sakit (House dkk dalam Maharani, 2015). g. Kepribadian Schmutte & Ryff (1997), Stell, Schmidt, & Schultz (2008), Ryff dkk. (2002) dalam penelitiannya mengenai hubungan lima tipe kepribadian (the big five traits) dengan dimensi-dimensi Psychological Well-Being menemukan bahwa sifat low neuroticism, exstravert, dan conscientiousness, berpengaruh pada psychological well-being khususnya pada penerimaan diri, penguasaan lingkungan dan tujuan hidup. Meskipun demikian aspek-aspek psycological well-being lain juga berkorelasi dengan kepribadian yang lainnya. Sifat keterbukaan terhadap pengalaman baru dan exstravert berpengaruh pada pertumbuhan diri, sedangkan agreeableness berpengaruh pada hubungan positif dengan orang lain, dan dimensi otonomi berkorelasi dengan beberapa kerpibadian namun yang paling menonjol adalah neurotik. 21 h. Spiritualitas Wink & Dillon (Maharani, 2015) menyatakan bahwa spiritualitas berkaitan dengan psycological well-being terutama pada aspek pertumbuhan pribadi dan hubungan positif dengaan orang lain. Spiritualitas merupakan sumberdaya dalam memertahankan psychological well-being, dimana individu yang merasa mendapatkan dukungan spiritual cenderung memiliki psychological well-being tinggi dan dapat mengurangi angka kematian (McClain, Rosenfeld, & Breitbart dalam Maharani, 2015). Dari beberapa penyataan di atas dapat disimpulkan bahwa faktorfaktor yang memengaruhi Psychological Well-Being adalah usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dukungan sosial, status sosial ekonomi, budaya, kepribadian dan spiritualitas. 4. Narapidana Wanita Menurut KUHP pasal 10 (dalam KUHP dan KUHP, 2002) narapidana adalah predikat lazim diberikan kepada orang yang terhadapnya dikenakan pidana hilang kemerdekaan, yakni hukuman penjara (kurungan). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia online, narapidana adalah orang yang hukuman atau terhukum, atau seseorang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana yang dilakukannya (Yudianto, 2011). Pada pasal 1 angka 7 Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 tantang permasyarakatan mengatakan bahwa, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Terpidana yang dimaksud 22 sesuai dengan Pasal 1 angka 6 undang-undang ini yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Harsono (dalam Riyadin, 2012) mengatakan bahwa narapidana adalah seseorang yang telah dijatukan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman atau sanksi, yang kemudian akan ditempatkan di dalam sebuah bangunan yang disebut rutan, penjara atau lembaga permasyarakatan. Tujuan dari menjalani pidana hilangnya kemerdekaan pada narapidana adalah untuk mengikuti proses pemasyarakatan. Maksud dari permasyarakatan dalam pasal 1 angka 1 UU Permasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan permasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemindanaan dalam tata peradilan pidana (Barda, 2008). Narapidana wanita yang dibina dalam lembaga pemasyarakatan disebut warga binaan pemasyarakatan atau klien pemasyarakatan. Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu, sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya 23 berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi (Barda, 2008). Berdasarkan beberapa defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa narapidana wanita merupakan seorang yang berstatus narapidana yang mengalami hilang kebebasan dan harus menjalani masa hukuman untuk mempertangungjawabkan perbuatannya, agar setelah selesai masa hukuman dapat memperbaiki perilakunya dan dapat kembali hidup bermasyarakat. 5. Dinamika Psychological Well-Being pada Narapidana Wanita di Lembaga Permasyarakatan Bagi wanita, menjadi narapidana merupakan suatu kondisi yang buruk dan dianggap bukan sekedar hukuman duniawi, tetapi juga hukuman Tuhan. Menurut KUHP pasal 10 (KUHP, 2002), narapidana adalah predikat lazim diberikan kepada orang yang terhadapnya dikenakan pidana hilang kemerdekaan, yakni hukuman penjara (kurungan). Pada pasal 1 ayat 7 Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dinyatakan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Terpidana dimaksud sesuai dengan Pasal 1 ayat 6 undang-undang ini yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap. Wanita yang telah masuk ke dalam Lembaga Permayarakatan akan mendapatkan stereotip buruk. Kondisi ini masih dianggap tabu oleh masyarakat, karena wanita lebih sedikit diberitakan melakukan tindakan 24 kriminal dibanding laki-laki. Masuknya narapidana ke dalam sel penjara menjadi suatu perubahan hidup yang akan berdampak pada kondisi fisik dan psikologis narapidana wanita. Sebagai pengalaman hidup yang penuh tekanan, narapidana mengalami efek-efek psikis dan psikologis yang buruk selama berada di Lapas (Pratama, 2016). Menurut Kartono (2009), isolasi yang lama karena disekap dalam penjara akan menyebabkan narapidana tidak memiliki partisipasi sosial, terkucilkan dan lekat dengan stigma-stigma negatif yang berkembang dalam masyarakat. Selain itu, narapidana akan didera oleh tekanan-tekanan batin yang semakin memberatkan dengan bertambahnya waktu pemenjaraan, munculnya kecenderungan-kecenderungan austistik (menutup diri secara total) dan usaha melarikan diri dari realitas yang bersifat traumatik. Para narapidana juga akan mengembangkan reaksi-reaksi emosional yang stereotipis, yaitu cepat curiga, mudah marah, cepat membenci dan pendendam. Menurut Bartol (Azani, 2012), dampak psikologis hukuman penjara antara lain: kehilangan identitas diri, stress, kecemasan hingga depresi, kehilangan rasa aman, kehilangan kebebasan untuk berkomunikasi, hilangnya pelayanan, kehilangan kasih sayang keluarga, kehilangan harga diri, kehilangan rasa percaya diri dan kehilangan kreatifitas bahkan impian serta cita-cita narapidana. Penolakan yang muncul dari keluarga dan masyarakat juga memerburuk kondisi psikologis narapidana. Hal ini akan memunculkan isolasi dan keengganan untuk berpartisipasi dalam lingkungan sosial 25 nantinya. Permasalahan-permasalahan tersebut menyebabkan ketidaknyamanan sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan psikologis wanita yang menjadi narapidana. Tujuan dari menjalani pidana dengan hilangnya kemerdekaan pada narapidana adalah untuk mengikuti proses pemasyarakatan. Maksud dari pemasyarakatan dalam pasal 1 ayat 1 UU adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana (Barda, 2008). Perbedaan antara kehidupan di luar Lapas dan kehidupan di dalam Lapas akan membawa sejumlah perubahan kehidupan termasuk kondisi narapidana, khususnya wanita. Psychological well-being bagi narapidana, merupakan kondisi yang penting agar bisa tetap menjalani kehidupannya di dalam Lapas dengan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki (Azani, 2012). Individu yang mencapai psychological well-being akan mampu memelihara kebahagiaan, kesehatan mental positif, dan pertumbuhan diri selama ada di dalam Lapas. Psychological well-being ditunjukkan dengan dimensi penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, otonomi, penguasaan lingkungan, tujuan hidup dan pertumbuhan pribadi (Ryff dalam Azani, 2012). Dimensi penerimaan diri diperoleh terlebih dahulu melalui adaptasi terhadap diri sendiri sampai individu mampu menerima dengan baik setiap kondisi yang dialaminya (Aini & Asiyah, 2013). Masa penerimaan diri atas 26 pembinaan pada narapidana wanita ini berkisar rentang waktu tiga sampai enam bulan. Semua responden mulai bisa beradaptasi dan mengenali lingkungannya, ini adalah upaya individu untuk menjadikan masa lalu sebagai pelajaran hidup dan mau memerbaiki diri (Pratama, 2016). Penerimaan diri positif dapat menjadikan narapidana menerima keadaan dirinya sebagai seorang tahanan di Lapas, merasa bahwa dirinya masih mampu berbuat sesuatu yang berguna walaupun berada di dalam Lapas, serta memandang positif segala kejadian di masalu sebagai teguran dari Tuhan agar invidu kembali ke jalan yang benar untuk memerbaiki diri menjadi pribadi lebih baik. Sebaliknya jika narapidana memiliki penerimaan diri negatif akan menjadikan narapidana merasa sangat menyesali masa lalu dan merasa tidak puas dengan dirinya. Hal itu membuat individu merasa ketidak bebasan dan jauh dari lingkungan sosialnya selama berada di dalam Lapas. Narapidana dengan dimensi hubungan sosial yang baik menurut Yudianto (2011) akan menjadikan individu semakin dekat dengan keluarga masing-masing. Keluarga menjadi lebih perduli dengan mereka dibandingkan sebelum masuk ke dalam Lapas. Selain itu mereka juga mampu, tidak segan dan tidak menutup diri untuk menjalin relasi mendalam dengan orang lain yang berada di dalam Lapas, misalnya dengan teman sesama narapidana atau petugas di Lapas. Individu lebih banyak menjalin interaksi dengan lingkungan sekitarnya dan belajar untuk memahami setiap karakter orang lain agar komunikasi antara mereka tidak saling menyakiti dan berjalan lancar. Adapun individu dengan hubungan negatif dengan orang lain akan sulit 27 bersikap hangat, terbuka dan menjalin hubungan dekat dengan orang lain, baik itu dengan keluarga, kerabat ataupun teman-teman sesama narapidana serta petugas di dalam Lapas. Mereka menjadi kurang ramah, suka menyendiri dan tidak memedulikan orang lain. Dimensi menentukan otonomi dirinya, individu memiliki dapat kemampuan berupa individu mengatur mampu perilaku atau tingkahlaku sesuai dengan norma yang ada serta dapat menahan tekanan sosial disekitarnya (Ryff, 1995). Otonomi positif akan menjadikan individu mampu mengambil keputusan sesuai dengan keyakinan sendiri, walaupun orang lain tidak sependapat dengannya, tidak mudah terpengaruh pendapat orang lain, tenang dalam menyelesaikan masalah dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, mereka pun tidak terpengaruh oleh pendapat orang lain. Adapun individu dengan otonomi yang rendah tidak mampu untuk memertahankan keyakinannya sendiri dan ketika mengambil keputusan seringkali dipengaruhi orang lain. Selain itu individu merasa takut apabila mengambil keputusan sesuai dengan pandangan diri sendiri, karena ia menghayati bahwa pendapat orang lain lebih benar daripada pendangannya. Individu dengan dimensi penguasaan lingkungan yang tinggi mampu menciptakan situasi yang membuatnya merasa nyaman meskipun berada di dalam Lapas, misalnya dalam upaya mengatasi stress mereka akan melakukan kegiatan seperti olahraga dan mengikuti pengajian. Upaya ini dilakukan agar mereka mampu mengatur emosi dengan baik dan stabil (Pratama, 2016). Adapun individu dengan penguasaan lingkungan yang rendah tidak akan 28 mampu menciptakan situasi di dalam lapas, individu seringkali bingung dan tidak tahu harus melakukan kegiatan apa di Lapas jika sudah tidak ada hal atau kewajiban yang harus dilakukan sehingga mereka cenderung menarik diri dan lebih memilih untuk mengisi waktu dengan tidur. Individu dengan tujuan hidup yang jelas akan memiliki kebermaknaan hidup yang baik meskipun menyandang status sebagai narapidana dan memiliki tujuan yang telah ditetapkan untuk masa depan. Masalah yang menimpa mereka dan keadaan yang mereka jalani sekarang merupakan titik balik dari kesalahan di masa lalu, kesempatan keadaan yang mewajibkan bersikap dan berperilaku baik sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka memiliki optimisme untuk menyambut kehidupan mereka yang baru (Handayani, 2010). Adapun individu dengan tujuan hidup yang tidak jelas merasa tidak memiliki kebermaknaan hidup serta tidak berarti karena menyandang status sebagai narapidana. Dimensi pertumbuhan pribadi yang tinggi akan membuat individu terus mengembangkan potensi dirinya dengan mengikuti berbagai kegiatan dan mau mencoba mengerjakan hal baru yang tidak pernah dilakukan sebelumnya, misalnya kegiatan kerajinan tangan dan menjahit. Hal ini akan menyadarkan bahwa mereka memiliki potensi dan kemampuan untuk mengerjakan hal tersebut. Adapun narapidana dengan pertumbuhan pribadi rendah merasa tidak mampu mengembangkan potensi diri dan tidak terbuka terhadap hal baru, tidak mau mengikuti kegiatan pengembangan diri di Lapas. 29 Psychological well-being pada narapidana ditandai dengan rasa memiliki penerimaan diri yang baik, memiliki hubungan positif dengan orang lain, kemandirian, tujuan hidup, penguasaan lingkungan serta pertumbuhan pribadi. Psychological well-being juga dipengaruhi berbagai faktor, yaitu usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan pekerjaan, status sosial ekonomi, budaya, dukungan sosial, dan spritualitas (Ryff, 1989). Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut Dalam hal usia, berdasarkan penelitian Ryff (1989), Ryff & Keyes (1995), Ryff & Singer (1996) penguasaan lingkungan dan kemandirian akan meningkat seiring bertambahnya usia, khususnya dari masa dewasa muda ke dewasa madya. Pada masa dewasa madya, individu sudah memiliki berbagai pengalaman dalam hidupnya, dan mereka juga melakukan evaluasi mengenai apa yang telah mereka lakukan dalam hidupnya, sehingga mereka bisa mengetahui lingkungan seperti apa yang sesuai bagi diri mereka dan dapat menyelesaikan tugas kompleks dalam hidupnya. Dengan keadaan seperti inilah, maka dimensi penguasaan lingkungan dapat meningkat di usia dewasa madya (Ryff,1996). Begitu juga dengan narapidana yang telah berada di usia dewasa madya, mereka dapat mencari strategi penyelesaian masalah kompleks dalam hidup mereka kerena pemikiran dan pengalaman mereka juga sudah berkembang. Selain itu, pada masa dewasa madya juga memiliki standar hidup pribadi dan tidak mengikuti standar orang lain. Hal ini dapat membuat individu bisa menghadapi berbagai masalah dan menyelesaikannya 30 sesuai dengan keyakinannya sendiri. Keadaan seperti ini dapat membuat dimensi otonomi meningkat (Ryff dalam Maharani, 2015). Sama halnya dengan narapidana, mereka telah memiliki standar hidup pribadi sehingga pada saat menjalani masa tahanan, mereka dapat menyelesaikan masalah sesuai dengan keyakinannya sendiri dan tidak terpengaruh oleh orang lain. Pengaruh usia pada psychological well-being individu juga dapat dilihat pada dimensi lainnya, yaitu pertumbuhan pribadi dan tujuan hidup yang mengalami penurunan dari usia dewasa madya ke dewasa lanjut, kesehatan dan beberapa fungsi kognitif pada individu dapat mengalami penurunan (Ryff dalam Maharani 2015). Begitu juga pada narapidana yang berada di usia lanjut, kesehatan dan beberapa fungsi kognitif yang menurun, akan membuat mereka mengalami hambatan untuk mengembangkan diri misalnya ketika mengikuti kegiatan kegiatan baru seperti membuat kerajinan tangan, mereka akan sulit untuk melakukannya. Faktor budaya ikut berperan dalam menentukan psychological wellbeing seseorang. Ryff & Singer (1996) menyatakan bahwa sistem nilai individualistik dan kolektivitas yang dianut oleh suatu masyarakat akan memberi dampak terhadap perkembangan psychological well-being seseorang. Narapidana yang menganut sistem individualistik, ketika dalam masa tahanan mereka akan dapat menunjukkan kemampuan dalam menyelesaikan masalahnya sendiri, tidak bergantung dan mengandalkan orang lain. Mereka mengandalkan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan yang mereka miliki untuk dapat berhasil menyelesaikan berbagai hal yang 31 mereka hadapi. Dengan keberhasilan yang mereka capai tersebut, mereka juga akan lebih menilai diri secara positif dan lebih mampu menerima diri mereka yang sekarang dengan apa adanya. Adapun narapidana yang menganut nilai kolektivitas, pada masa tahanan akan senang melakukan kegiatan bersama dengan orang lain. Misalnya dengan mengikuti kegiatan kerajinan tangan dengan sesama teman narapidana yang lain. Selain itu, walaupun berada dalam Lapas mereka akan berusaha untuk tetap menjalin hubungan yang dekat dengan keluarga. Hal ini menjadikan dimensi hubungan positif dengan orang lainnya menjadi tinggi. Perbedaan status kelas sosial ekonomi turut memengaruhi psychological well-being, yaitu dalam dimensi penerimaan diri, tujuan hidup, penguasaan lingkungan, dan pertumbuhan pribadi (Ryff dalam Ryan & Deci, 2001). Faktor yang tercangkup di dalamnya meliputi pendidikan, pendapatan dan pekerjaan. Melalui penelitian longitudinal terhadap sampel dewasa madya, didapatkan hasil bahwa tingkat well-being individu akan lebih baik bila memiliki status pendidikan dan pekerjaan yang tinggi. Begitu juga dengan narapidana yang memiliki status pendidikan dan pekerjaan yang tinggi sebelum masuk ke lapas. Dengan ilmu pengetahuan dan pengalam sebelumnya mereka miliki tentunya mereka akan dapat menguasai lingkungan dan mengoptimalkan pengembangan dirinya. Faktor dukungan sosial, menurut Davis (Praiwi, 2000) dinyatakan bahwa individu yang mendapatkan dukungan sosial memiliki tingkat psychological well-being yang lebih tinggi. Dukungan sosial dapat diartikan 32 sebagai rasa nyaman, perhatian, penghargaan ataupun pertolongan yang dipersepsikan oleh seorang individu didapat dari diri orang lain atau kelompoknya. Dalam hal ini narapidana walaupun berada di dalam Lapas tetap mendapatkan dukungan emosional berupa, perhatian, keperdulian dan empati dari orang lain, misalnya dari keluarga, akan tetap merasa nyaman dicintai walaupun berstatus sebagai narapidana Hal ini dapat membuat psychological well-being cenderung menjadi tinggi. Dukungan penghargaan berpengaruh terhadap psychological wellbeing. Narapidana yang selama menjalani masa tahanan tetap dihargai oleh keluarganya akan menunjukkan psychological well-being yang cenderung tinggi dibandingkan dengan narapidana yang mendapat perlakuan verbal negatif dari keluarganya yang kemudian dapat membuatnya kehilangan perasaan dihargai (Yudianto, 2011). Faktor lain yang memengaruhi psychological well being adalah spiritualitas. Penelitian yang dilakukan mengenai psikologi dan religiusitas yang dilakukan oleh Ellison & Levin (1998), Ellison dkk (2001), Koenig (2004), Krause & Ellison (2003) menemukan hubungan positif antara religiusitas dengan dimensi penerimaan diri dan petumbuhan pribadi yang dimiliki seorang individu. Narapidana yang lebih aktif dalam kegiatan keagamaan cenderung memiliki tingkat psychological well-being yang tinggi dan hal ini akan berdampak pada tingginya persepsi rasa penguasaan lingkungannya, serta dapat meningkatkan self esteem nya. Hal ini juga dapat menjadikan prediktor evaluasi kepuasan hidupnya. 33 Dilihat dari dimensi dan faktor-faktor yang memengaruhi keberadaan psychological well-being pada narapidana dapat berefek negatif atau positif pada individu. Efek negatif akan muncul dan menghambat perkembangan dan dapat menimbulkan ketidakberdayaan diri. Jika hal ini muncul keberadaannya akan mengakibatkan individu hanya mampu menerima keadaan apa adanya tanpa ada usaha dari dirinya untuk membuat hidupnya menjadi lebih baik. Adanya psychological well-being yang tinggi dalam diri individu, khususnya narapidana yang sedang menjalani masa tahanan, akan membuat individu mampu menghadapi kodisi yang sedang dijalani. B. Pertanyaan Penelitian Pertanyaan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Psychological well-being pada narapidana wanita di Tanjungpandan Belitung.. Lapas gambaran Klas IIB