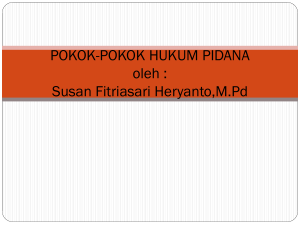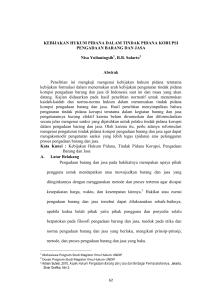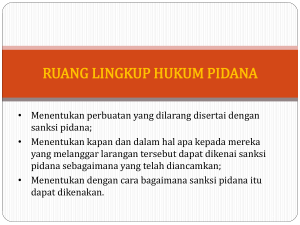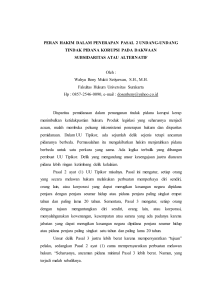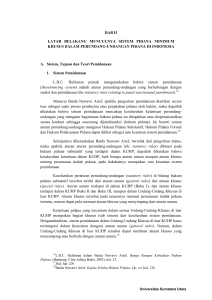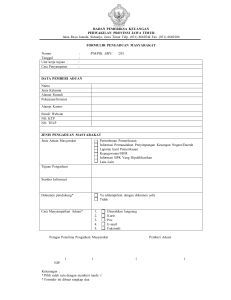BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah
advertisement

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itulah umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga. Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuhkembangkan potensi yang ada pada setiap individu, dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan atau aktivitas ilegal lain sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya seperti penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan. Situasi inilah yang lazim disebut dengan istilah Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi wacana tersendiri dalam keseharian. Pada umumnya, dalam struktur kekerabatan di Indonesia kaum lakilaki ditempatkan pada posisi dominan, yakni sebagai kepala keluarga. Dengan demikian, bukan hal yang aneh apabila anggota keluarga lainnya menjadi sangat tergantung kepada kaum laki-laki. Posisi laki-laki yang demikian superior sering kali menyebabkan dirinya menjadi sangat berkuasa di tengah-tengah lingkungan keluarga. Bahkan pada saat laki-laki melakukan berbagai penyimpangan kekerasan terhadap anggota keluarga lainnya dimana perempuan dan juga anak menjadi korban utamanya tidak ada seorang pun dapat menghalanginya. Oleh 1 2 karena itu para aktivis dan pemerhati perempuan sangat memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Hal ini sangat dipahami bahwa bukan saja Konstitusi Indonesia telah secara tegas dan jelas melindungi hak-hak asasi manusia dan perlindungan terhadap tindakan diskriminasi, namun kejadian-kejadian KDRT dengan berbagai modus operandinya, mengakibatkan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) menderita, pada umumnya mereka menjadi stress, depresi, ketakutan, trauma, takut bertemu pelaku, cacat fisik, atau berakhir pada perceraian. Dari sisi pelaku, apabila kasusnya terungkap dan dilaporkan, biasanya timbul rasa menyesal, malu, dihukum, dan atau memilih dengan perceraian pula. Sehingga memerlukan pengaturan yang memadai, termasuk perlindungan terhadap bentuk-bentuk diskriminasi hak asasi perempuan dalam rumah tangga. Bangsa Indonesia patut merasa bersyukur, karena pada tanggal 22 September 2004 pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang diharapkan dapat dijadikan sebagai perangkat hukum yang memadai, yang didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga. Menurut UU RI No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Secara umum Undang-Undang ini menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945. Apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh undang-Undang 3 ini adalah meminimalisir tindak pidana KDRT dan pada akhirnya adalah terwujudnya posisi yang sama dan sederajat di antara sesama anggota keluarga. Posisi yang seimbang antara suami dan istri, anak dengan orang tua, dan juga posisi yang setara antara keluarga inti dengan orang-orang yang baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi bagian dari keluarga sementara saat itu dalam keluarga. Seperti pembantu rumah tangga maupun sanak saudara yang kebetulan tinggal dalam keluarga tersebut dengan tidak memberi pembatasan apakah mereka laki-laki atau perempuan. Sekalipun kaum laki-laki terkesan aktor yang paling banyak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tidak berarti kekerasan dalam rumah tangga tidak pernah dilakukan oleh kaum wanita (ibu) terhadap anggota keluarga lainnya. Masyarakat seolah-olah menganggap bahwa kekerasan yang dilakukan sang istri terhadap suaminya dalam rumah tangga adalah suatu kewajaran karena merupakan bagian dari dinamika kehidupan berumah tangga yang biasa terjadi, dan menganggap bahwa sang suami akan mampu menghadapi dan mengatasinya. Laki-laki secara fisik dianggap lebih kuat daripada perempuan, sehingga apabila suatu saat hal tersebut terjadi (kekerasan terhadap suami) sang suami bukannya mendapat motivasi atau dukungan moril dari orang terdekatnya tapi justru malah suami mendapat tekanan tambahan dari orang-orang sekelilingnya yang menganggapnya sebagai laki-laki pengecut, cupu (culun), lemah di hadapan perempuan, tidak mampu mengendalikan istri dan sebagainya. Sebagai contoh kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangga terhadap suami yang terjadi belum lama ini namun tidak terekspose karena kasus tersebut 4 akhirnya dicabut pengaduannya oleh korban sendiri. Pada kejadian kekerasan dalam rumah tangga tersebut sang istri menyiramkan air panas ke tubuh suaminya hingga kulitnya melepuh. Keluarga sang suami yang tidak terima dengan perbuatan istri korban tersebut melaporkannya ke Polisi, namun pengaduan tersebut dimentahkan oleh suami pelaku dengan dalih sangat mencintai istrinya dan menurut korban wajar jika pelaku (istri) berbuat demikian kepadanya karena penghasilan korban tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Akhirnya pelaku (istri) tidak ditahan karena korban (suami) mencabut pengaduan tersebut. Hal ini membuktikan tidak hanya wanita atau istri dan anak-anak yang dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga tetapi juga kaum pria atau suami. Dari kasus tersebut juga dapat dilihat kelemahan dari delik aduan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dimana meskipun sudah jelas-jelas perbuatan yang dilakukan pelaku adalah tindak pidana dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia namun tanpa adanya pengaduan dari korban maka pelaku tidak dapat dituntut atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga hanya beberapa pasal dari tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (yang tergolong ringan) yang menjadi delik aduan, selebihnya merupakan delik biasa (berdasarkan pasal 15 UU PKDRT). Tetapi pada prakteknya, karena sulitnya membuktikan dan menemukan saksi, maka kemudian menjadi delik aduan. Demi terwujudnya keadilan dan jaminan kepastian hukum perlu adanya kejelasan bahwa tindakan-tindakan kekerasan internal rumah tangga bukan hanya merupakan “delik aduan” tetapi “delik pidana umum”. 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bertujuan memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Tetapi pada kenyataannya, perlindungan yang diberikan belum memadai, terutama karena sanksi bagi pelaku yang tidak tepat. Dilihat dari sudut politik kriminil, maka tidak terkendalinya perkembangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang semakin meningkat, justru dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang dipilih dan ditetapkan. Terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut yang tidak dapat dilaksanakan karena sanksi hukum yang tidak sesuai dan tidak ada peraturan pelaksanaannya seperti rumah aman dan rumah alternatif bagi korban KDRT. Selain itu juga dengan sistem sanksi alternatif yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 bagi masyarakat pada umumnya yang awam di bidang hukum dapat menimbulkan salah tafsir dimana mereka yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dapat memilih penjatuhan sanksi bila tidak ingin dipenjara maka dapat dengan membayar pidana denda saja maka mereka akan bebas dari jeratan hukum. Selain itu, pencantuman sanksi maksimal saja tanpa mencantumkan batas minimal dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Pelaku bisa saja hanya dijatuhi dengan pidana paling minimun dan ringan bagi korban yang tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga korban enggan untuk mengadukan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya yang dianggap akhirnya hanya akan membuang-buang waktu dan tidak dapat memenuhi rasa keadilan korban. 6 Dari latar belakang tersebut maka penulisan ini dimaksudkan untuk menganalisis rumusan kebijakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penelusuran lebih dalam terhadap ketentuan pidana dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan menganalisa delik aduan serta hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pemidanaan yang terkandung di dalamnya yang merupakan titik penting dalam menentukan strategi perencanaan politik kriminal. Menentukan tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan dalam rangka penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kebijakan menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan, setidak-tidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi. Masalah pemilihan berbagai alternatif untuk memperoleh pidana mana yang dianggap paling baik, paling tepat, paling patut paling berhasil atau efektif merupakan masalah yang tidak mudah. Keaslian dari penulisan tesis ini dapat dilihat melalui perbandingan terhadap tesis sebelumnya yang juga mengangkat mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Adapun beberapa judul tesis sebelumnya yaitu : “Studi Kriminologi Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur”, yang dibuat oleh Lamber Missa, SH. dari Universitas Diponegoro tahun 2010, dengan rumusan masalah : 1). Bagaimana Fenomena kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Kupang?, 2). Bagaimana Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditinjau dari aspek 7 kriminologi?, 3). Bagaimana perspektif Masyarakat Kota Kupang terhadap fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pola Penyelesaiannya?. Judul Tesis “Peran Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana KDRT” yang dibuat oleh Anda Nurani, SH. dari Universitas Sumatera Utara Medan tahun 2008, rumusan masalahnya : 1). Bagaimanakah peran Polri dalam Penanggulangan tindak pidana KDRT?, 2). Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi Polri dalam upaya menanggulangi tindak pidana KDRT?, 3). Bagaimanakah solusi bagi Polri dalam upaya menganggulangi KDRT di masa mendatang?. Judul Tesis “Pencabutan Delik Aduan Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Akibatnya Dalam Peradilan Pidana” yang dibuat oleh Astrya Umacy Saragih dari Universitas Sumatera Utara tahun 2010, dengan rumusan masalah : 1). Bagaimana hubungan antara KUHP, KUHAP dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?, 2). Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan dari pencabutan pengaduan tersebut dan mengapa institusi penegak hukum melanjutkan proses penyidikan, penuntutan bahkan sampai menjatuhkan hukuman.?. Judul Tesis “Tinjauan Yuridis Perlindungan Saksi Sekaligus Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Komparatif Antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban)” yang dibuat oleh Thunang Prihambodo, SH., dari Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2008, dengan rumusan masalah : 1) Bagaimanakah perbandingan perlindungan saksi sekaligus korban kekerasan dalam rumah tangga antara Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang 8 Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban?, 2). Bagaimanakah fungsi dan peran Lembaga-Lembaga terkait. Judul Tesis ”Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Dalam Lingkup Perkawinan Sirri dan Upaya Perlindungan Hukumnya”, yang dibuat oleh Alifia Puspita Wulansari, S.H., dari Universitas Airlangga tahun 2008, dengan rumusan masalah : 1). Apakah perbuatan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan yang hubungan perkawinannya melalui kawin sirii termasuk dalam ruang lingkup Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2004 ?, 2). Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan yang hubungan perkawinannya menggunakan kawin secara siri jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga ?. Sedangkan Tesis ini berjudul “Analisis Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Undang-Undang No. 23 tahun 2004), dengan rumusan masalah : 1). Bagaimanakah kebijakan formulatif terhadap tindak pidana dalam tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga?, 2). Bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam perumusan sistem sanksi pidana terhadap tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga?. Dilihat dari judulnya dan kajian permasalahan tesis ini dengan tesis-tesis yang sebelumnya mengkaji permasalahan dari sudut pandang yang berbeda, sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini dapat dijamin keasliannya dan dapat dipertanggung jawabkan dari segi isinya. 9 1.2. Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah kebijakan formulatif terhadap tindak pidana dalam tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga ? 2. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam perumusan sistem sanksi pidana terhadap tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga ? 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1. Tujuan Penelitian 1.3.1.1. Tujuan Umum Tujuan penelitian secara umum yaitu untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam undang-undang KDRT dalam rangka penanggulangan KDRT, untuk pengembangan konsep ilmu hukum pidana secara umum, dan untuk pemahaman yang tidak hanya terpaku pada dogmatik hukum tapi juga pengembangan asas, teori hukum pidana. 1.3.1.2. Tujuan Khusus 1. Untuk melakukan analisis terhadap kebijakan hukum pidana (Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga) dalam merumuskan tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. 2. Untuk melakukan analisis terhadap kebijakan hukum pidana (Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga) dalam perumusan sistem sanksi pidana terhadap tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. 10 1.3.2. Manfaat Penelitian 1.3.2.1. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan menambah bahan pustaka mengenai analisis terhadap kebijakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga (Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga). 1.3.2.2. Manfaat Praktis Adapun manfaat praktis dari penulisan ini, yaitu : Sebagai sumbangan pemikiran untuk penyelesaian masalah dalam kasuskasus konkrit sehingga dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum di dalam penyelesaian kasus-kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangga. 1.4. Landasan Teoritis Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan namun kejahatan tersebut tidak pernah sirna dari muka bumi, bahkan semakin meningkat cara hidup manusia maupun teknologi semakin canggih pula ragam dan pola kejahatan yang muncul. Tidak hanya di Indonesia saja, pada dasarnya setiap masyarakat yang telah maju dan masyarakat pada masa modern ini berkepentingan untuk mengendalikan kejahatan dan mengurangi serendah mungkin angka kejahatan melalui berbagai alternatif penegakan hukum.1 1 Widiyanti, Ninik dan Panji Anoraga, 1987, Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya, Pradnya Paramita, Jakarta. h. 58. 11 Keadaan ini mendorong diusahakannya berbagai alternatif untuk mengatasi kejahatan - kejahatan tersebut, baik oleh para penegak hukum maupun oleh para ahli-ahli hukum dan kriminologi. Berbagai Elemen yang ada hubungannya dengan suatu kejahatan dikaji dan dibahas secara intensif seperti : para pelaku (daders), para korban, pembuat undang-undang dan undang-undang, penegak hukum, dan lain-lain. Dengan kata lain semua fenomena baik maupun buruk yang dapat menimbulkan kriminilitas (faktor kriminogen) diperhatikan dalam meninjau dan menganalisa terjadinya suatu kejahatan. Namun tidak dapat dipungkiri selama ini dalam menganalisa maupun dalam menangani suatu peristiwa kejahatan perhatian tercurah pada pelaku kejahatan saja. Sedikit sekali perhatian diberikan pada korban kejahatan yang sebenarnya merupakan elemen (partisipan) dalam peristiwa pidana. Si korban tidaklah hanya merupakan sebab dan dasar proses terjadinya kriminilitas tetapi memainkan peranan penting dalam usaha mencari kebenaran materil yang dikehendaki hukum pidana materil. Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. 1. Viktimologi Menurut Arif Gosita, salah satu latar belakang pemikiran viktimologis ini adalah “pengamatan meluas terpadu”. Menurut beliau segala sesuatu harus diamati secara meluas terpadu (makro-integral) di samping diamati secara mikroklinis, apabila kita ingin mendapatkan gambaran kenyataan menurut proporsi 12 yang sebenarnya secara dimensional, mengenai sesuatu, terutama mengenai relevansi sesuatu.2 Setidak-tidaknya dapat ditegaskan bahwa apabila kita hendak mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya dari berbagai dimensi (secara dimensional) maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peranan korban (victim) dalam timbulnya suatu kejahatan. Selanjutnya pemahaman tentang korban kejahatan ini baik sebagai penderita sekaligus sebagai faktor/elemen dalam suatu peristiwa pidana akan sangat bermanfaat dalam upayaupaya pencegahan terjadinya tindak pidana itu sendiri (preventif). Suatu tindakan kejahatan (crime) mesti melibatkan dua pihak yaitu si pelaku kejahatan (perpetraktor) dan si korban (victim). kriminalitas itu adalah suatu hasil intraksi karena adanya interrelasi antara yang ada dan saling mempengaruhi. Dengan demikian adalah suatu hal yang tidak berlebih-lebihan bila dalam kasus-kasus tertentu maupun secara umum bahwa pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama-sama, bertanggung jawab atau tidak, secara aktif atau pasif, dengan motivasi positif atau negatif. Semuanya bergantung pada situasi dan kondisi pada saat atau sebelum kejahatan itu berlangsung. Dengan demikian kita akan dapat menentukan sikap dan mengambil tindakan yang tepat dalam masalah korban dan pelayanannya maupun dalam menentukan suatu hukum bagi pelayanan kejahatannya. 2. Hukum Pidana 2 Gosita, Arief, 1986, Victimologi dan KUHAP, Akademika Pressindo, Jakarta, h. 8. 13 Menurut para ahli bahwa hukum adalah suatu kaidah yang bersifat memaksa dan apabila ada orang melanggar kaidah itu diancam dengan sanksi yang tegas dan nyata.3 Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Menurut Moeljatno, hukum pidana mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk : 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.4 Rumusan di atas agak panjang dan memerlukan sekedar penjelasan sebagai berikut : a. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. b. Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, (kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut) untuk singkatnya kita menamakan perbuatan pidana atau delik.5 3 4 5 Suharto, 1991, Hukum Pidana Materiil, Unsur-unsur Objektif sebagai Dasar Dakwaan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, h. 3. Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, h. 1-2. Ibid, h. 2. 14 Dibedakan pula pengertian melawan hukum formil dan materiil. Menurut Pompe, dari istilahnya saja sudah jelas, melawan hukum (Wederrech telijk) jadi bertentangan dengan hukum, bukan bertentangan dengan Undang-undang. Dengan demikian, Pompe memandang “melawan hukum” sebagai yang kita maksud dengan “melawan hukum materiil”. Ia melihat kata on rechtmatic, (bertentangan dengan hukum) sinonim dengan wedwerhechtelijk (melawan hukum) sesuai dengan pasal 1365 BW. Sama dengan pengertian Hoge Raad dalam perkara Cohen-Lindenbaum (HR 31 Januari 1919 N. J. 1919 hlm. 161 W. 10365), yang juga meliputi perbuatan bertentangan dengan hukum tidak tertulis, yang bertentangan dengan kepatutan, dipandang melawan hukum. Sedangkan melawan hukum secara formil diartikan bertentangan dengan Undang-undang. Apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik, maka biasanya dikatakan telah melawan hukum secara formil. Melawan hukum materiil harus berarti hanya dalam arti negatif, artinya kalau tidak ada melawan hukum (materiil) maka merupakan dasar pembenar. Dalam penjatuhan pidana harus dipakai hanya melawan hukum formil, artinya yang bertentangan dengan hukum positif yang tertulis, karena alasan asas nullum crimen sine lege stricta yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.6 c. Tentang Penentuan Perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, kita menganut asas yang dinamakan asas legalitas (principle of legality), yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan Undang-undang (Pasal 1 ayat 1 KUHP). 6 Andi Hamzah, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, h. 132-133. 15 d. Barang siapa melakukan perbuatan pidana diancam dengan pidana. Akan tetapi ini belum berarti bahwa tiap-tiap orang yang melakukan perbuatan tersebut lalu mesti dipidana. Sebab untuk memidana seseorang disamping melakukan perbuatan yang dilarang dikenal asas yang berbunyi : “Green Straf Zonder Schuld”. Jerman : “Keine Straf Ohne Schuld”, dalam hukum pidana Inggris asas ini dikenal dalam bahasa latin yang berbunyi : Actus non Facit, Nisi Mens sit rea. (An Act does not make a person quilty, unless the mind is quilty). Asas tersebut tidak kita dapati dalam KUHP sebagaimana halnya dengan asas legalitas.7 Hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana tidak dapat dipidana dapat terletak pada orangnya sendiri yang diatur dalam Pasal 44 KUHP (karena tidak mampu bertanggung jawab yang disebabkan karena jiwanya terganggu oleh suatu penyakit atau karena pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna / cacat dalam tubuhnya). Pada dasarnya hukum pidana berpangkal pada dua hal yaitu : a. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu Dengan “perbuatan yang memenuhi syarat-syarat”, tersebut dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan seperti itu dapat disebut sebagai “perbuatan pidana” atau juga dapat disebut sebagai “perbuatan jahat” (verbrechen atau dalam istilah dalam bahasa Inggris sebagai crime), oleh karena dalam “perbuatan” ini harus ada orang yang melakukannya, maka persoalan tentang perbuatan tertentu 7 Moeljatno, Op.Cit, h. 5. 16 tersebut dapat dijabarkan menjadi dua persoalan yaitu perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu. b. Pidana Yang dimaksud pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.8 Ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana : a. Sifat melawan hukum b. Kesalahan (schuld) c. Pidana (stafe).9 Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undangundang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (subjective guilt). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya harus dapat dipertanggungkan kepada orang tersebut.10 There are five decision criteria used to determine if an incident involves a violation of the criminal law. An exploration of these criteria will demonstrate the problems inherent in the legal scheme of crime classification. To be considered a crime, an act must : (1) be observable, 8 9 10 Moeljatno, Op.Cit, h. 5. Muladi dan Prijatno, 1991, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, (selanjutnya disebut Muladi I), h. 56. Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, (Selanjutnya disebut Sudarto I), h. 85. 17 (2) be a violation of either statute or case law, (3) have a prescribed punishment called for in law. Concerning the actor : (4) he or she must intend to commit a crime, (5) he or she must be acting without defense or justification.11 Ada lima kriteria keputusan yang digunakan untuk menentukan apakah suatu insiden melibatkan suatu pelanggaran hukum pidana. Eksplorasi kriteria ini akan menunjukkan masalah yang melekat dalam skema hukum dari klasifikasi kejahatan. Untuk dipertimbangkan sebagai suatu kejahatan, suatu perbuatan harus : patut diperhatikan, merupakan pelanggaran hukum baik undang-undang atau kasus, memiliki hukuman yang ditentukan dalam hukum. Mengenai aktor : maka dia harus mempunyai niat untuk melakukan kejahatan, ia harus bertindak tanpa pembelaan atau pembenaran. Meskipun kriteria ini mungkin tampak mudah, namun agak sulit dalam aplikasinya. Salah satunya yaitu karena dalam masyarakat kita, kita tidak dapat dituntut untuk apa yang kita pikirkan tetapi dapat dituntut hanya jika ada perbuatan yang terbukti melanggar hukum yang berlaku. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana sebagaimana diancam, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah : Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (Geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sir rea). Asas ini tidak tersebut dalam KUHP tapi dalam kenyataannya juga berlaku di Indonesia. Untuk menjatuhkan pidana, dijumpai beberapa pendapat antara lain : 11 James F. Gilsinan, 1990, Criminology and Public Policy An Introduction, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, h. 20. 18 1. Vos menjelaskan bahwa tanpa sifat melawan hukumnya perbuatan tidaklah mungkin dipikirkan adanya kesalahan, namun sebaliknya sifat melawan hukumnya perbuatan mungkin ada tanpa adanya kesalahan. 2. Moeljatno menyatakan lebih baik dengan kalimat, bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana. 3. Jonkers di dalam keterangan tentang “schuldbegrip” membuat bagian atas tiga bagian dalam pengertian kesalahan yaitu : a. Selain kesengajaan atau kealpaan (opzet of schuld); b. Meliputi juga sifat melawan hukum (de wederrechtelijkheid); c. Dan kemampuan bertanggung jawab (de toerekenbaarheid). 4. Pompe berpendapat bahwa pengertian kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela (verwijtbaarheid) yang pada hakekatnya tidak mencegah (vermijdbaarheid) kelakuan yang bersifat melawan hukum (der wederrechtelijke gedraging). 5. E. Mezger, yang mempunyai pandangan yang dapat disimpulkan mengenai pengertian kesalahan terdiri atas : a. Kemampuan bertanggungjawab (zurechnungsfahig) b. Adanya bentuk kesalahan (schuldform) yang berupa kesengajaan (vorzatz) dan culpa (fahrlassigkeit) c. Tak ada alasan penghapus kesalahan (keinen schuldausschiesungsgrunde). 19 Pandangan Vos dan Mezger terakhir tentang pengertian kesalahan ini mempunyai kesamaan tanpa mencampuradukkan elemen melawan hukum dibidang kesalahan.12 Dari pendapat-pendapat tersebut di atas maka dapatlah dikatakan bahwa kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Jadi orang yang bersalah melakukan perbuatan itu berarti bahwa perbuatan itu dapat dicelakakan kepadanya. Pencelaan disini bukan pencelaan berdasarkan kesusilaan, melainkan pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku. Menurut Sudarto untuk adanya kesalahan maka harus ada pencelaan ethis, betapa pun kecilnya. Setidaknya pembuat dapat dicela karena tidak menghormati tata dalam masyarakat, yang terdiri dari sesama hidupnya dari yang membuat segala syarat untuk hidup bersama. Pernyataan bahwa kesalahan itu mengandung unsur ethis (kesusilaan) tidak boleh dibalik. Tidak senantiasa orang, yang melakukan perbuatan atau orang yang tidak menghormati tata ataupun kepatuhan dalam masyarakat atau pada umumnya melakukan perbuatan yang dapat dikenakan tindak susila itu dapat dikatakan bersalah dalam arti dicela menurut hukum.13 Mengenai beberapa bentuk kesalahan yang dalam bahasa Belanda disebut dengan “opzet”, Satochid memberikan perumusan opzet itu sebagai melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak.14 12 13 14 Bambang Poernomo, 1992, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, h. 135-137. Sudarto I, Op.cit, h. 89. Cansil Christine, 2004, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 5051. 20 Dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tahun 1809 dicantumkan : “kesengajaan adalah kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undangundang” Dalam Memorie Van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan Crimineel Wetboek tahun 1981 (yang menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia Tahun 1915), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (de bewuste richting van den wil op een bapaald misdrijf).15 Mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan apa yang dimaksud dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui) adalah : Seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu.”16 Beberapa pakar merumuskan de wil sebagai “keinginan, kemauan, atau kehendak”. Dengan demikian, perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. Kehendak (de wil) dapat ditujukan terhadap : a. Perbuatan yang dilarang; b. Akibat yang dilarang. Dahulu dikenal dolus molus yang mengartikan kesengajaan (opzet) sebagai perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsyafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman.17 15 Leden Marpaung, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, h. 13. Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, Bandung, h. 16 291. 17 Laden Marpaung, Op. Cit, h. 13. 21 Menurut M.v.T kealpaan di suatu pihak lain dengan hal yang kebetulan. Sedangkan kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan akan tetapi bukannya kesengajaan yang ringan.18 Menurut doktrin, schuld yang sering diterjemahkan sengan “kesalahan” terdiri atas : 1. Kesengajaan, dan 2. Kealpaan. Kedua hal tersebut dibedakan, “kesengajaan” adalah dikehendaki, sedang “kealpaan” adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari “kesengajaan”. Itulah sebabnya, sanksi atau ancaman hukuman terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan dengan “kealpaan”, lebih ringan. Simons menerangkan “kealpaan” tersebut sebagai berikut : “Umumnya kealpaan itu terdiri dari dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang Undangundang. Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduganya akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan. Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya “dapat diduga lebih dahulu” itu harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman, terdapat kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada.”19 Dengan adanya syarat yang pertama itu maka diletakkan hubungan antara batin terdakwa dengan akibat yang timbul karena perbuatannya, atau keadaan yang 18 19 Laden Marpaung, Op. Cit, h. 124. Titaamidjaja, 1955, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Fasco, Jakarta, h. 55. 22 menyertainya. Perbuatan yang telah dilakukan terdakwa itu seharusnya dapat dihindarkan, karena seharusnya ia menduga terlebih dahulu bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat yang dilarang. Si terdakwa dapat dicela dengan terjadinya perbuatan tersebut. Dapat dicelanya ini karena ia telah tidak mengadakan dugaan sebagaimana diharuskan oleh hukum. Dugaan mengenai akan terjadinya akibat atau keadaan yang menyertainya tidaklah perlu senyatanya ada dalam psyche terdakwa. Selama pandangan orang telah berubah dari pandangan yang psikologis kepada pandangan yang normatif mengenai kesalahan maka mengenai sikap batin itu tidak perlu kalau senyatanya ada dalam psyche terdakwa, yang cukup kalau hubungan itu oleh hukum dipernilai ada atau tidak ada. Pentingnya menentukan adanya hubungan batin ini adalah agar dapat mempertanggungjawabkan si terdakwa atas akibat yang ditimbulkan atas kelakuan itu. Bukanlah tidak mungkin, bahwa hubungan batin tersebut tidak ada sama sekali. Artinya akibat yang terjadi tidaklah mungkin diduga-duga olehnya. Tidak mungkin ini baik secara subyektif menurut keadaan psyche terdakwa sendiri, maupun secara obyektif tidaklah dapat diharuskan oleh hukum padanya untuk menduga tentang akan terjadinya akibat. Begitu pula sebaliknya, yaitu dari adanya hubungan batin ini, maka harus pulalah ada hubungan kausal. Artinya harus adanya hubungan lahir antara perbuatan terdakwa dan akibat yang dilarang. Bahkan dapat dikatakan bahwa hubungan kausal inilah yang merupakan soal pertama yang harus dipecahkan. Apabila hubungan kausal antara kelakuan dan akibat saja sudah dipandang tidak 23 ada maka tidaklah perlu dipertimbangkan mengenai hubungan kesalahannya, sekalipun kita mengakui bahwa terdakwa telah sangat ceroboh. Hubungan kausal antara kelakuan dan akibat adalah sesuatu dalam bidang menentukan perbuatan pidana, sedangkan kesalahan adalah dalam bidang pertanggungjawaban pidana. Apabila hal yang menentukan perbuatan pidana telah tidak ada (dalam hubungan ini hubungan kausal antara kelakuan dan akibat) maka tidak perlu untuk dipertimbangkan mengenai hubungan kesalahannya. Dalam hal kealpaan ini, dengan tambahan sekalipun kita mengakui bahwa terdakwa sangat ceroboh. Syarat lainnya untuk adanya kesalahan adalah tidak ada alasan pemaaf, artinya untuk dapat dikatakan seseorang adalah bersalah, maka orang tersebut : (1) Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum, (2) Mampu bertanggungjawab, (3) Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau kealpaan, (4) Tidak ada alasan pemaaf. Apa maksud dengan hal yang terakhir ini yaitu alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan dari terdakwa. Jadi tidak adanya alasan pemaaf tentu berarti tidak adanya alasan untuk menghapuskan kesalahan dari terdakwa. Menurut Sudarto alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya melawan hukum. Jadi disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan.20 20 Sudarto I, Op.cit, h. 139. 24 Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa ketiga unsur dalam kesalahan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan yang satu bergantung pada yang lain, dalam arti demikianlah urutan-urutannya dan yang disebut kemudian bergantung pada yang disebutkan terlebih dahulu. Konkritnya tidak mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan atau kealpaan, apabila orang itu tidak mampu bertanggung jawab. Begitu pula tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf apabila orang itu tidak mampu bertanggung jawab, dan tidak pula adanya kesengajaan ataupun kealpaan. 3. Kebijakan Hukum Pidana Berbicara mengenai kebijakan hukum pidana, tentunya tidak terlepas dari pengertian kebijakan itu sendiri, dalam kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan, dan cara bertindak (pemerintah, organisasi) dan pernyataan cita-cita tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, halauan. Sementara itu, Marc Ancel menyatakan bahwa : Kebijakan pidana (penal policy) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada si pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan dan juga para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang.21 Sudarto pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu : 21 Barda Nawawi, 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, (Selanjutnya disebut Barda Nawawi I), h. 23. 25 a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana; b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; c. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan normanorma sentral dari masyarakat. 22 Dalam kesempatan lain beliau mengemukakan definisi singkat, bahwa politik kriminal merupakan "suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan".23 Istilah kebijakan diambil dari istilah “policy” (Inggris) atau “politiek” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “penal policy”, “criminal law policy” atau ”strafrechtspolitiek”. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Prof. Sudarto, “Politik Hukum” adalah : a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.24 b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa 22 23 24 Ibid, h. 1. Sudarto, 1981, Hukum dan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, (Selanjutnya disebut Sudarto II), h. 38. Ibid, h. 159. 26 digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.25 Bertolak dari pengertian demikian Prof. Sudarto selanjutnya menyatakan bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.26 Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti, “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.27 Senada dengan pernyataan di atas, Solly Lubis juga mengatakan bahwa politik hukum pidana adalah kebijaksanaan politik yang menentukan peraturan hukum apa seharusnya berlaku mengatur berbagai kehidupan masyarakat dan bernegara.28 Mahfud M.D., juga memberikan definisi politik hukum sebagai kebijakan mengenai hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Hal ini juga mencakup pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu.29 Dalam konteks ini hukum tidak hanya bisa dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataannya bukan tidak mungkin 25 26 27 28 29 Sudarto, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, (Selanjutnya disebut Sudarto III), h. 20. Sudarto II, Op.cit, h. 161. Sudarto III, Op.cit, h. 93 dan 109. Solly Lubis, 1989, Serba Serbi Politik dan Hukum, Mandar Maju, Bandung, h. 19. Mahfu, 1998, Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, h. 2. 27 sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materinya (pasal-pasal), maupun dalam penegakannya. Berdasarkan pengertian tentang politik hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa politik hukum pidana merupakan upaya menentukan ke arah mana memberlakukan hukum pidana Indonesia masa yang akan datang dengan melihat penegakannya di masa kini. Hal ini juga berkaitan dengan konseptualisasi hukum pidana yang paling baik untuk diterapkan. A. Mulder mengemukakan secara rinci tentang ruang lingkup politik hukum pidana yang menurutnya bahwa politik hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan : 1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dilakukan perubahan atau diperbaharui; 2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya kejahatan; 3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.30 Berdasarkan pengertian politik hukum pidana yang dikemukakan oleh A. Mulder di atas, maka ruang lingkup kebijakan hukum pidana ini sesungguhnya meliputi masalah yang cukup luas, yaitu meliputi evaluasi terhadap substansi hukum pidana yang berlaku saat ini untuk pembaharuan substansi hukum pada masa yang akan datang, dan bagaimana penerapan hukum pidana ini melalui komponen Sistem Peradilan Pidana, serta yang tidak kalah pentingnya adalah upaya pencegahan terhadap kejahatan. Upaya pencegahan ini berarti bahwa 30 Barda Nawawi I, Op.cit, h. 23. 28 hukum pidana juga harus menjadi salah satu instrumen pencegah kemungkinan terjadinya kejahatan. Ini juga berarti bahwa penerapan hukum pidana harus mempunyai pengaruh yang efektif untuk mencegah sebelum suatu kejahatan terjadi. Oleh karena itu kelemahan atau kesalahan kebijakan pidana dapat dipandang sebagai kesalahan yang sangat strategis, karena hal ini dapat menghambat penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (social defence) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Dengan demikian, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (sosial policy). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.31 Dengan demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kebijakan hukum pidana sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum. Dalam hal ini arti penegakan hukum itu sendiri adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginankeinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Dengan demikian perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan 31 Ibid, h. 27. 29 menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.32 Dalam hal ini peranan peraturan hukum sangat besar kaitannya dengan pelaksanaan peraturan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dapat diartikan pula bahwa keberhasilan atau kegagalan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya telah dimulai sejak peraturan hukum tersebut dibuat. Misalnya, badan legislatif atau instansi yang berwenang membuat peraturan tersebut telah membuat peraturan yang sulit dilaksanakan oleh masyarakat, sejak saat itulah awal kegagalan produk peraturan yang dibuat oleh badan tersebut. Hal ini dapat diakibatkan dalam peraturan tersebut memerintahkan sesuatu hal yang tidak didukung oleh sarana yang mencukupi, akibatnya, peraturan tersebut gagal untuk dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.33 4. Teori Feminis Kekerasan dalam rumah tangga identik dengan kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan berbasis gender karena dominan korbannya adalah perempuan. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga banyak bermunculan aliran-aliran feminisme berupa gerakan pembebasan perempuan yang mengupayakan transformasi bagi suatu pranata sosial yang secara gender lebih adil. Tujuan ini didasarkan pada kesadaran dan kenyataan bahwa sistem patriarki yang berlaku pada mayoritas masyarakat manusia di dunia sesungguhnya secara gender tidak adil dan menindas terutama terhadap perempuan. 32 33 Satjipto Raharjo, 2005, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, CV. Sinar Baru, Bandung, h. 24. Ibid, h. 25. 30 Jaggar dan Rothenberg mengkategorikan teori feminis ke dalam empat kategori :34 1. Feminis Liberal (Liberal feminism) Asumsi dasar pemikiran aliran ini adalah faham liberalisme, yaitu bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan serasi dan seimbang (struktural fungsional), karena itu harusnya tidak terjadi penindasan antara satu dengan yang lainnya. Penindasan terjadi karena rendahnya intelektual perempuan akibat kurangnya kualitas pendidikan dan tidak meratanya kesempatan. 2. Feminis Marxis (Marxist Theories) Asumsi dasar pemikiran aliran ini adalah adanya penindasan berdasarkan kelas, khususnya dikaitkan dengan cara kapitalisme menguasai perempuan dalam kedudukan yang direndahkan. Ketertinggalan perempuan bukan karena disebabkan oleh tindakan individu secara sengaja, tetapi akibat struktur sosial politik dan ekonomi yang erat kaitannya dengan sistem kapitalisme. 3. Feminis Sosialis (Socialist Feminism) Aliran ini merupakan sintesis antara Feminis Marxis dan Feminis Liberal. Asumsi dasar pemikirannya adalah bahwa hidup dalam masyarakat kapitalis bukan satu-satunya penyebab ketertinggalan perempuan. Aliran ini lebih memperhatikan keanekaragaman bentuk patriarki dan pembagian kerja secara seksual karena menurut mereka kedua hal ini tidak dapat dilepaskan dari aktivitas produksi. 34 Munandar Sulaeman, Siti Homzah, 2010, Kekerasan terhadap Perempuan (Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 6. 31 4. Feminis Radikal (Radical Theories) Asumsi yang mendasari aliran ini adalah pemikiran bahwa ketidakadilan gender yang menjadi akar dari tindak kekerasan terhadap perempuan justru terletak pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan itu. Jenis kelamin seseorang adalah faktor paling berpengaruh dalam menentukan posisi sosial, pengalaman hidup, kondisi fisik, psikologis, kepentingan, dan nilai-nilainya. Karena itu aliran ini menggugat semua lembaga yang dianggap merugikan perempuan seperti institusi keluarga dan sistem patriarki, karena keluarga dianggap sebagai institusi yang melahirkan dominasi sehingga perempuan ditindas dan mengalami kekerasan. Antisipasi kekerasan terhadap perempuan telah banyak dilakukan baik oleh kelembagaan formal (pemerintah) maupun kelembagaan informal (LSM, Organisasi Masyarakat maupun Organisasi Politik). Upaya yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam rangka menghilangkan kekerasan terhadap perempuan dilakukan dengan mengelaborasi realitas sosial, sebagai hasil konstruksi fakta sosial yang diciptakan oleh nilai patriarki. Kondisi kultur patriarki saat ini sudah mulai banyak digugat, mulai dari interpretasi kembali nilai sosial budaya dan cara penafsiran nilai agama. Hasilnya menunjukkan adanya kelompok yang pemahaman gendernya sudah memadai, sehingga berpengaruh terhadap antisipasi kekerasan. Upaya yang dilakukan sekarang sudah sesuai melalui proses pelembagaan seperti dilakukan pada obyektivikasi UndangUndang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga). Pada aspek pola relasional masih terjadi praktik-praktik 32 hubungan sosial yang mengedepankan faktor kekuasaan secara fisik (power) atau kekuasaan kewenangan yang mengatur hubungan atasan dan bawahan secara diskriminatif, seperti terjadi pada buruh pekerja, pembantu rumah tangga atau pada keluarga yang dapat bermuara pada kekerasan. Di balik keberhasilan proses pelembagaan tata nilai atau anti kekerasan, masih dirasakan adanya kelemahan dalam hal infrastruktur dan ketersediaan sumber daya manusianya yang masih terbatas sensitivitas gendernya baik secara kualitas maupun kuantitas. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dewasa ini korbannya tidak hanya perempuan dan anak-anak tetapi laki-laki pun dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. “One reaction to the official statistics has been to seek to explain why the rate for women is less than that for men and to look for reasons why women engage less in criminal activity. There are many different approaches to this issue : - Individualistic explanations - Traditional approaches to female crime - Structural feminist explanations - patriarchy”35 Salah satu reaksi terhadap statistik resmi telah mencari untuk menjelaskan mengapa tingkat perempuan kurang dari pria dan untuk mencari alasan mengapa perempuan kurang terlibat dalam kegiatan kriminal. Ada pendekatan yang berbeda untuk masalah ini : - Penjelasan Individualistis Awal teori kejahatan wanita cenderung fokus pada penjelasan biologis atau psikologis. Beberapa feminis berpendapat bahwa teori yang sangat 35 Tony Lawson & Tim Heaton, 1999, Crime and Deviance, Macmillan Press LTD, England, h. 201. 33 awal seperti Lombrstoso dan Freud menyarankan bahwa wanita menyimpang adalah mereka yang paling menyukai atau ingin menjadi laki-laki dan kejahatan itu disebabkan karena biologis. Namun interpretasi karya Lambroso telah menjadi topik dari beberapa feminis. Brown berpendapat bahwa Lambroso telah salah mengartikan dan bahwa apa yang dia benar-benar nyatakan adalah bahwa kecenderungan biologis perempuan adalah untuk penyesuaian, bukan kejahatan. Wanita yang melanggar hukum bukan 'tindak pidana kodrat', tetapi dalam kata-kata Lambroso, 'pelanggar sesekali', dan bukan wanita tapi pria yang cenderung untuk melakukan tindak pidana. - Pendekatan Tradisional untuk kejahatan wanita Faktanya bahwa perempuan diperlakukan berbeda dalam kehidupan bermasyarakat, contohnya tidak memiliki kebebasan yang sama dengan laki-laki. Aturan yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan pun berbeda, sebagai contoh : perempuan bukan pencari nafkah utama. - Penjelasan Struktural feminis Ada dua faktor struktural mengapa perempuan cenderung tidak berbuat kejahatan, yaitu : pengelompokan sosialisasi ke dalam sistem nilai yang berbeda (interaksi perempuan ditandai dengan keterlibatan kasih sayang dan empati dan dengan demikian juga dalam kejahatan, khususnya kejahatan kekerasan), dan kontrol sosial (perempuan memiliki kesadaran yang lebih besar terhadap resiko ditangkap, yang mempengaruhinya untuk tidak melakukan kejahatan. 34 - Patriarki Memfokuskan pada kekuatan laki-laki dalam masyarakat dan sistem peradilan pidana yang sangat didominasi oleh laki-laki dengan asumsi dan agenda untuk menindas perempuan yang menjalani proses peradilan pidana. 5. Teori Pemidanaan Secara global dan representatif pada pokoknya “sistem pemidanaan” atau “the sentencing system” mempunyai 2 (dua) dimensi hakiki, yaitu : Pertama, dapat dikaji dari perspektif pemidanaan itu sendiri. Menurut Ted Honderich, maka pemidanaan mempunyai 3 (tiga) anasir, yaitu : 1. Pemidanaan harus mengandung semacam kehilangan (deprivation) dan kesengsaraan (distress) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pemidanaan. Unsur pertama ini pada dasarnya merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita oleh subjek yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan sadar subyek lain. Secara aktual, tindakan subjek lain itu dianggap salah bukan saja karena mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, tetapi juga karena melawan hukum yang berlaku secara sah. 2. Setiap pemidanaan harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum pula. Jadi, pemidanaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku-pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Karenanya, pemidanaan bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan. 3. Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pemidanaan hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya. Unsur ketiga ini memang mengundang pertanyaan tentang “hukuman kolektif”, misalnya embargo ekonomi yang dirasakan juga oleh orang-orang yang tidak bersalah. Meskipun demikian, secara umum pemidanaan dapat dirumuskan terbuka sebagai denda (penalty) yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada pelanggar hukum atau peraturan.36 36 Yong Ohoitimur, 1997, Teori Etika Tentang Hukuman Legal, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 2-3. 35 Kedua, sistem pemidanaan juga melahirkan eksistensi ide individualisasi pidana. Pada pokoknya ide individualisasi memiliki beberapa karakteristik tentang aspek-aspek sebagai berikut : Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal); b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas : “tiada pidana tanpa kesalahan”); a. c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.37 Memang, hakikatnya untuk saat ini kebijakan pidana (criminal policy) pada kebijakan legislatif terlebih lagi khususnya kebijakan pemidanaan dalam takaran aplikatif diperlukan dan mendesak sifatnya. Ada beberapa aspek mengapa kebijakan ini perlu dirumuskan, yaitu : Pertama, untuk sedapat mungkin diharapkan relatif menekan adanya disparitas dalam pemidanaan (disparity of sentencing) terhadap kasus atau perkara yang sejenis, hampir identik dan ketentuan tindak pidana yang dilanggar relatif sama. Pada hakekatnya, disparitas menurut Molly Cheang merupakan penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (same offence) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (offences of comparable seriousness) tanpa dasar pembenaran yang jelas.38 Dengan adanya pedoman pemidanaan pada kebijakan legislatif maka hakim dalam hal penerapan peraturan sebagai kebijakan aplikatif dapat menjatuhkan pidana lebih adil, manusiawi dan mempunyai rambu37 38 Barda Nawawi I, h. 43. Molly Cheang, 1977, Disparity of Sentencing, Singapore Malaya Law Journal, PTE Ltd., Singapore, h. 2. 36 rambu yang bersifat yuridis, moral justice dan sosial justice. Konkritnya, konsekuensi logis aspek ini maka putusan hakim atau putusan pengadilan diharapkan lebih mendekatkan diri pada keadilan yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Akan tetapi, kenyataannya di Indonesia tidak ada pedoman pemidanaan yang dapat sebagai barometer dan katalisator bagi hakim. Aspek ini ditegaskan oleh Sudarto sebagai berikut : “KUHP kita tidak memuat pedoman pemberian pidana (straftoemetingsleiddraad) yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana yang ada hanya aturan pemberian pidana (straftoemetingsregels).”39 Kedua, pedoman pemidanaan memberikan ruang gerak, dimensi dan aktualisasi kepada hakim dalam hal menerangkan undang-undang sebagai kebijakan legislatif sesuai dengan nuansa apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Aspek ini penting sifatnya oleh karena sebenarnya kebijakan legislatif merupakan kebijakan yang bersifat strategis dan menentukan oleh karena kesalahan dalam kebijakan legislatif akan berpengaruh besar kepada kebijakan aplikatif yang diterapkan di lapangan. Oleh karena itu tentu diperlukan sikronisasi, transparansi dan latar belakang yuridis tentang hakekat apa dari suatu undang-undang, apa yang diinginkan oleh pembentuk undang-undang terkonkretisasi sehingga hakim sebagai kebijakan aplikatif tidak salah menerapkan dan mewejahwantahkan undang-undang. Ketiga, pedoman pemidanaan memberikan dan berfungsi sebagai katalisator guna menjadi “katup pengaman” bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa agar hakim dapat menjatuhkan putusan secara lebih adil, arif, manusiawi dan relatif memadai 39 Molly Cheang, Op.cit, h. 4. 37 terhadap kesalahan yang telah dilakukan terdakwa. Oleh karena itu, dengan adanya pedoman pemidanaan tersebut maka diharapkan di samping ditemukan keadilan yang dapat diterima semua pihak juga tercermin adanya nilai kepastian hukum (rechts-Zekerheids) yang dijatuhkan hakim dalam putusannya. One of the purposes of criminal punishment is to change the behavior of the offender by associating negative reinforcements, such as fines and detention, with misbehavior. Arrest also counts as a negative reinforcement. For any criminal contemplating a crime, prison time is the most disagreeable but also least probable foreseeable consequence of his anticipated transgression.40 Salah satu tujuan dari hukuman pidana adalah untuk mengubah perilaku buruk pelaku dengan penegakan hukum negatif, seperti denda dan penahanan. Penangkapan juga termasuk sebagai penegakan hukum negatif. Untuk merenungkan pidana kejahatan, penjara adalah yang paling tidak menyenangkan tetapi juga sedikit konsekuensi akan kemungkinan pelanggaran yang akan terjadi. Barda Nawawi Arief dan Muladi menyatakan bahwa hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pemidanaan adalah titik penting dalam menentukan strategi perencanaan politik kriminal. Menentukan tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan.41 Kebijakan menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan, setidak-tidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi. Masalah pemilihan berbagai alternatif untuk memperoleh pidana mana yang dianggap paling baik, paling tepat, paling patut paling berhasil atau efektif merupakan masalah yang 40 41 Daniel D. Polsby, 1992, Suppressing Domestic Violence with Law Reforms, Northwestern University School of Law, USA, h. 250. Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.cit, h. 95. 38 tidak mudah. Dilihat dari sudut politik kriminil, maka tidak terkendalinya perkembangan kriminalitas yang semakin meningkat, justru dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang dipilih dan ditetapkan.42 Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam perumusan tujuan pemidanaan adalah43 : Pada hakekatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang a) bertujuan sehingga dirumuskan pidana dan aturan pemidanaan dalam undang-undang, pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan, b) Dilihat secara fungsional operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkretasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahap. Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, maka dirumuskan tujuan pemidanaan, c) Perumusan tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai ”fungsi pengendalian kontrol” dan sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah. 44 Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. 42 43 44 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.cit, h. 89. Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, (Selanjutnya disebut Barda Nawawi II), h. 113-114. Barda Nawawi I, Op.cit, h. 136-137. 39 Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan. Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pemidanaan menjadi 3 kelompok yakni : a) Teori absolut (retributif) Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. b) Teori teleologis Teori teleologis (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. c) Teori retributif teleologis. Teori retributif-teleologis memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. 45 45 Muladi I, Op.cit h. 49-51. 40 Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution yang bersifat utilitarian dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Karena tujuannya bersifat integratif, maka perangkat tujuan pemidanaan adalah : 1) Pencegahan umum dan khusus; 2) Perlindungan masyarakat; 3) Memelihara solidaritas masyarakat 4) Pengimbalan/pengimbangan. Secara lebih rinci Muladi menyatakan bahwa restorative justice model mempunyai beberapa karakteristik yaitu : a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik; b. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan; c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi; d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama; e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil; f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial; 41 g. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif; h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab; i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik; j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif. Restorative justice model diajukan oleh kaum abolisionis yang melakukan penolakan terhadap sarana koersif yang berupa sarana penal dan diganti dengan sarana reparatif.46 Paham abolisionis menganggap sistem peradilan pidana mengandung masalah atau cacat struktural sehingga secara relatistis harus dirubah dasar-dasar sruktur dari sistem tersebut. Dalam konteks sistem sanksi pidana, nilai-nilai yang melandasi paham abolisionis masih masuk akal untuk mencari alternatif sanksi yang lebih layak dan efektif daripada lembaga seperti penjara.47 Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas 46 47 Muladi, 1996, Kapita Seleksi Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, (Selanjutnya disebut Muladi II), h. 125. Romli Atmasasmita, 1996, Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Binacipta, Bandung, h. 101. 42 secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini. Restorative justice membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka. Restorative justice juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Kemudian restorative justice juga mengupayakan untuk merestore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah sense of control. 1.5. Metode Penelitian Agar suatu karya tulis dapat dikatakan sebagai suatu karya yang bersifat ilmiah, hendaknya haruslah menggunakan suatu metode. Metode merupakan cara/jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Dengan demikian, metode dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian; 2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan; 3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Dengan demikian dari pengertian metode tersebut, dapat diartikan sebagai 43 suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sementara ini penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.48 Menurut Tyrus Hillway, penelitian dapat diartikan sebagai semua metode ilmiah yang dilakukan melalui penyelidikan yang sesama dan lengkap terhadap semua bukti-bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu, dengan demikian dapat diperoleh suatu pemecahan bagi permasalahan itu.49 Metode penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian, atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. 50 Metode penilitian adalah hal yang sangat penting dalam suatu penelitian ilmiah, karena nilai, mutu dan hasil dari suatu penelitian ilmiah, sebagian besar ditentukan oleh ketepatan dalam penelitian metodenya. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.5.1. Jenis Penelitian Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga sebagai penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. 48 49 50 Khudzaifah Dimyanti dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah), UMS, Surakarta, h. 1. Khudzaifah Dimyanti dan Kelik Wardiono, Op.cit, h. 2. Rianto Adi, 2004, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta, h. 1. 44 Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan. Hal ini disebabkan karena penelitian lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian kepustakaan demikian dapat pula dikatakan sebagai lawan dari penelitian empiris.51 Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulisan pada tesis ini dilakukan dengan menggunakan penelitian normatif dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan peraturan hukum negara lain dalam rangka penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). 1.5.2. Metode Pendekatan Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan terhadap Undang-Undang yaitu dengan menganalisa kebijakan hukum pidana dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam hal perumusan tindak pidana serta sistem sanksi pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Disamping itu juga dilakukan dengan pendekatan perbandingan dengan ketentuan hukum dari negara lain untuk dapat memahami bagaimana hukum negara lain dalam perumusan tindak pidana serta sistem sanksi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Pendekatan konsep yaitu dengan menganalisis konsep-konsep hukum yang ada yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. 1.5.3. Sumber Bahan Hukum 51 Bambang Waluyo, 2010, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, h. 13. 45 Sumber bahan hukum atau data yang diperlukan dalam penyusunan tesis ini adalah bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diuraikan dalam rumusan masalah. Adapun bahan hukum yang digunakan : 1.5.3.1. Bahan hukum primer Yaitu bahan hukum yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah. 52 Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan tesis ini, yaitu : 1. Undang-undang Nomer 23 tahun 2004 tentang 2006 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun Perlindungan Saksi dan Korban. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. 4. Nomor Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan : 01 Tahun 2006 tentang Forum Koordinasi Penyelenggaraan Kerja Sama Pencegahan dan Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 1.5.3.2. Bahan hukum sekunder 52 Burhan Ashshofa, 2001, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, h. 103. 46 Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang isinya membahas bahan hukum primer. 53 Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam tesis ini antara lain buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini, kamus hukum, dan artikel di internet. 1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah : Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu dengan membuat catatan-catatan yang diperoleh dari literatur-literatur dan perundangundangan yang terkait dengan penulisan tesis ini. Pencatatan dilakukan dengan menggunakan sistem kartu. Lazimnya dikenal dua macam kartu yang perlu disiapkan untuk mencatat data, yakni : a. Kartu kutipan, dipergunakan untuk mencatat/ mengutip data beserta sumber darimana data tersebut diperoleh. b. Kartu bibliografi, dipergunakan untuk mencatat sumber bacaan yang dipergunakan. Kartu ini sangat penting dan berguna pada waktu menyusun daftar kepustakaan sebagai bagian penutup laporan penelitian yang ditulis. 54 Pada penulisan tesis ini penulis menggunakan kartu kutipan guna mengumpulkan data kepustakaan. 1.5.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum Pengolahan bahan hukum adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan bahan hukum di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis. 53 54 55 Burhan Ashshofa, Op.cit, h. 104. Bambang Waluyo, Op. Cit, h. 54. Bambang Waluyo, Op. Cit, h. 72. 55 47 Beranjak dari judul penulisan maka teknik pengolahan bahan hukum dengan pendekatan normatif, analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan (normatif), pada tahap ini akan dilakukan inventarisasi hukum terhadap kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Undang-Undang No. 23 tahun 2004), dan asas-asas hukum. Data yang telah teridentifikasi tersebut kemudian diorganisir kedalam suatu sistem yang komprehenif, berdasarkan kategori-kategori hukum tertentu, setelah sebelumnya dilakukan pengoleksian terhadap keseluruhan asas-asas dan normanorma hukum yang terkumpul tersebut. Setelah tahapan inventarisasi, selanjutnya mendiskusikan data sekunder yang telah terkumpul dengan data hasil inventarisasi mengenai kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Undang-Undang No. 23 tahun 2004). Dengan demikian pada tahap akhirnya ditemukan perumusan tindak pidana serta sanksi pidana yang diatur di dalam UU No. 23 tahun 2004. Bahan hukum yang dihimpun dari studi pustaka kemudian dikumpulkan dan diklasifikasikan berdasarkan substansinya kemudian diuraikan dan dihubungkan dengan teori-teori yang bersumber dari literatur. Setelah itu disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan secara jelas dan sistematis permasalahan yang dibahas dan kemudian dianalisa secara kualitatif untuk dapat diambil kesimpulannya. Analisa kualitatif dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus.56 Argumentatif, dari 56 Rianto Adi, Op. Cit, h. 128. 48 kesimpulan tersebut kemudian penulis memberikan pendapat hukum terhadap analisa bahan hukum tersebut. BAB II PENGERTIAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA, TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 2.1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana 49 Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan sejahtera merata materiil dan sprituil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Salah satu bagian pembangunan nasional adalah pembangunan dibidang hukum, yang dikenal dengan istilah pembaharuan hukum (law reform). Pembaharuan hukum nasional sebagai bagian dari rangkaian pembangunan nasional ini dilakukan secara menyeluruh dan terpadu baik hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum administrasi, dan meliputi juga hukum formil maupun hukum materielnya. Upaya pembaharuan hukum tidak terlepas dari kebijakan publik dalam mengendalikan dan membentuk pola sampai seberapa jauh masyarakat diatur dan diarahkan. Dengan demikian sangat penting untuk menyadarkan para perancang hukum dan kebijakan publik bahkan para pendidik, bahwa hukum dan kebijakan publik yang diterbitkan akan mempunyai implikasi yang luas di bidang sosial, ekonomi dan politik. Sayangnya spesialisasi baik dalam pekerjaan, pendidikan maupun riset yang dilandasi dua disiplin tersebut (hukum dan ilmu sosial), sehingga berbagai informasi yang bersumber dari keduanya tidak selalu bertemu (converge) bahkan seringkali tidak sama dan sebangun (incongruent). 1. Pengertian Kebijakan Berdasarkan keistilahan, kebijakan antara lain diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam 50 pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran garis haluan.57 Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris policy atau dalam bahasa Belanda politie. Black’s Law Dictionary mengidentifikasikan Policy sebagai: The general principles by which a government is guided in its management of public afairs, ...or principles and standard regarded by the ligislature or by the courts as being of fundamental concern to the state and the whole of society in measures, as applied to a law, ordinance, or rule of law, denotes its general purpose or tendency considered as directed to the welfare or prosperity of the state comunity.58 Secara umum, pengertian kebijakan sebagai pengganti dari istilah “policy” atau “beleid” khususnya dimaksudkan dalam arti “wijsbeleid”, menurut Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood, dapat dirumuskan sebagai suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara kolektif.59 Menurut Thomas R. Dye, kebijaksanaan disebut dengan ”Public Policy, is concerned with that governments do, why they do it, and what difference it makes”.60 Pemerintah menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menyangkut kepentingan umum dan untuk keperluan tersebut pemerintah 57 58 59 60 Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, h. 115. Henry Campbell Black, 1999, Black’s Law Dictionary, Seventh Edition, St.Paulmin West Publicing,Co., h. 117. Sultan Zanti Arbi dan Wayan Ardana, 1997, Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial, CV. Rajawali, Jakarta, h. 63 (terjemahan dari The Design of Sosial Policy tulisan Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood). Thomas R Dye, 1978, Understanding Public Policy, third Edition, Prentice Hall.Inc, Englewood Cliifss, NJ, h. 3. 51 mempunyai berbagai inisiatif penentuan langkah yang dengan singkat dirumuskan oleh Dye : ”Public policy is whatever governments choose to do or not to do”. Dalam merumuskan tujuan kebijaksanaan, pemerintah lazimnya menetapkan tujuan yang hendak dicapai, sebagaimana yang dinyatakan Friedrich : ”it is essential for the policy concept that there be a goal, objective, or purpose”.61 Dalam beberapa tulisan, ada pula yang menterjemahkan “policy” dengan kebijaksanaan, seperti Muhadjir Darwin menterjemahkan “publik policy analysis” karya William N. Dunn dengan “analisa kebijaksanaan publik”.62 Solichin Abdul Wahab juga menggunakan istilah Kebijaksanaan untuk menterjemahkan istilah “policy”. Akan tetapi di dalam bukunya yang berjudul “Analisa Kebijaksanaan”, beliau juga memakai istilah kebijakan untuk menterjemahkan istilah “policy”.63 Policy often describes general goals and general means for achieving them based on the commonly accepted values of a society. Statements that condemn evil and support good can be readily agreed to by most citizens.64 Kebijakan sering menggambarkan tujuan umum dan sarana umum untuk mencapai tujuan mereka berdasarkan nilai-nilai umum untuk diterima suatu masyarakat. Pernyataan yang mengutuk kejahatan dan dukungan yang baik dapat segera disetujui oleh sebagian besar warga. Meskipun pendapat tersebut berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya, memberikan arti yang sama tentang kebijakan/ policy /poilitiek / kebijaksanaan 61 62 63 64 Ibid William N. Dunn (Penyadur Muhadjir Darwin), 2000, Analisa Kebijaksanaan Publik, PT. Hadindita Graha Widia, Yogyakarta, Cet. 6, h. 37. Solichin Abdul Wahab, 1997, Kebijakan Sosial, Analisis Kebijakan, Edisi kedua, PT. Bumi Aksara, Jakarta, h. 24. James F. Gilsinan, Op.Cit, h.24. 52 yaitu suatu cara ataupun upaya untuk mencapai tujuan tertentu yang telah digariskan oleh suatu organisasi dengan cara tertentu agar mencapai hasil yang paling baik. Salah satu upaya atau usaha untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah melalui sarana hukum (kebijaksanaan hukum), dengan menuangkan kebijaksanaan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam peraturan perundanganundangan melalui hukum hukum pidana yaitu dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. 2. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana Menurut Bentham, “definition of law is commonly summarised as the command of a sovereign backed by a sanction, we see here the elements of : command, sovereignty, and sanction.”65 yang artinya : definisi hukum umumnya diringkas sebagai perintah dari yang berdaulat yang didukung oleh sanksi, kita lihat disini unsur-unsurnya yaitu perintah, kedaulatan, dan sanksi. Hukum dibuat oleh pemerintah yang berdaulat,yang mana ketentuan hukum tersebut mengandung sanksi berupa hukuman apabila ditentang. Istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “penal policy”, “criminal law policy” atau “strafrechtspolitiek”. Criminal policy as a science of policy is part of a larger policy : the law enforcement policy. this makes it understandable that administrative and 65 Hilaire McCoubrey and Nigel D. White, 1993, Textbook on Jurisprudence, Blackstone Press Limited, London, h. 13-14. 53 civil law occupy the same place in the diagram as non-criminal legal crime prevention. The legislative and enforcement policy is in turn part of social policy.66 Kebijakan hukum pidana sebagai ilmu kebijakan adalah bagian dari kebijakan yang lebih besar : kebijakan penegakan hukum. Hal ini membuat dimengerti bahwa hukum administrasi dan perdata menempati tempat yang sama dalam diagram sebagai pencegahan kejahatan di luar hukum pidana. Kebijakan legislatif dan penegakannya adalah bagian dari kebijakan sosial. Marc Ancel menyatakan bahwa kebijakan pidana (penal policy) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada si pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan dan juga para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang.67 Oleh karena itu kelemahan atau kesalahan kebijakan pidana dapat dipandang sebagai kesalahan yang sangat strategis, karena hal ini dapat menghambat penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (social defence) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Dengan demikian, wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (sosial policy). Kebijakan sosial dapat diartikan 66 67 G. Peter Hoefnagels, 1973, The Other Side of Criminology, Kluwer - Deventer, Holland, h. 57. Barda Nawawi I, Op.cit, h.23. 54 sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.68 Usaha pencegahan kejahatan adalah bagian dari politik kriminal, dimanapolitik kriminal (criminal policy) mempunyai tiga arti yaitu : a. keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa hukum pidana; b. keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; c. merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.69 Pencegahan dan pendekatan kejahatan dengan sarana “penal” merupakan “penal policy” atau “penal law enforcement policy” yang fungsionalisasi dan atau operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu : a. Formulasi (Kebijakan legislatif/legislasi) yaitu tahap penegakan hukum in abstracto untuk badan pembuat undangundang. b. Aplikasi (kebijakan yudikatif/yudicial)70 Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. c. Eksekusi (kebijakan eksekutif/administrasi) Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. 68 69 70 Barda Nawawi I, Op.cit, h. 2. Sudarto, 1981, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung,(Selanjutnya disebut Sudarto IV), h. 114. Muladi II, Op.cit, h. 13-14. 55 Berkaitan dengan peran legislatif tersebut Nyoman Serikat Putra Jaya,71 menyatakan lembaga legislatif berpartisipasi dalam menyiapkan kebijakan dan memberikan kerangka hukum untuk memformulasikan kebijakan dan menerapkan program kebijakan yang telah diterapkan. Keseluruhannya itu, merupakan bagian dari kebijakan hukum atau politik hukum yang pada hakikatnya berfungsi dalam tiga bentuk, ialah: 1. Politik tentang pembentukan hukum; 2. Politik tentang penegakan hukum; dan 3. Politik tentang pelaksanaan kewenangan dan kompetensi. Walaupun ada keterkaitan erat antara kebijakan formulasi/legislasi (legislative policy khususnya penal policy) dengan law enforcement policy dan criminal policy, namun dilihat secara konseptual/teoritis dan dari sudut realitas, kebijakan penanggulangan kejahatan tidak dapat dilakukan semata-mata hanya dengan memperbaiki/memperbaharui sarana undang-undang (law reform termasuk criminal law/penal reform). Namun evaluasi tetap diperlukan sekiranya ada kelemahan kebijakan formulasi dalam perundang-undangan yang ada. Evaluasi terhadap kebijakan formulasi mencakup tiga masalah pokok dalam hukum pidana yaitu masalah perumusan tindak pidana (kriminalisasi), pertanggungjawaban pidana, dan aturan pidana dan pemidanaan. Perencanaan (planning) dalam penanggulangan kejahatan dengan sistem hukum pidana pada tahapan formulasi pada intinya mencakup tiga masalah pokok struktur sistem hukum pidana, yaitu masalah : 71 Nyoman Serikat Putra Jaya, 2006, Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana, Program Magister Ilmu Hukum, Undip, Semarang, h.13. 56 a. Perumusan tindak pidana/Kriminalisasi dan Pidana yang diancamkan (criminalization and threatened punishment) b. Pemidanaan (adjudication of punishment sentencing) c. Pelaksanaan pidana (execution of punishment) Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan : 1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan 2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Penganalisisan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosialpolitik yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah sentral di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach). Sudah barang tentu pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana, tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya. Bertolak dari pendekatan kebijakan itu pula, Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut :72 72 Sudarto II, Op.cit, h. 44-48. 57 a. Penggunaan hukum pidana harus memerhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas warga masyarakat c.Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (cost and benefit principle). d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting). Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. Untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak kriminal perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut : 58 a. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban. b. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai. c. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya. d. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat. Disamping kriteria umum di atas, perlu juga memperhatikan sikap dan pandangan masyarakat mengenai patut tercelanya suatu perbuatan tertentu, dengan melakukan penelitian, khususnya yang berhubungan dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial. Demikian pula menurut Bassiouni, keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor, termasuk :73 a. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai; b. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yanng diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari; dan 73 Cherif Bassiouni M., 1978, Substantive Criminal Law, h. 82. 59 c. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia; dan d. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder. Menurut G.P. Hoefnagels suatu politik kriminal harus rasional, kalau tidak demikian tidak sesuai dengan definisinya sebagai “a rational total of the responses to crime”. Disamping itu, hal ini penting karena konsepsi mengenai kejahatan dan kekuasaan atau proses untuk melakukan kriminalisasi sering ditetapkan secara emosional.74 Pendekatan yang rasional memang merupakan pendekatan yang seharusnya melekat pada setiap langkah kebijakan. Hal ini merupakan konsekuensi logis, karena dalam melaksanakan kebijakan, orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapinya. Ini berarti suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar. Ini berarti memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya. Dengan demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kebijakan hukum pidana sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum. Dalam hal ini arti penegakan hukum itu sendiri adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan74 Hoefnagels G.P., Op.cit, h. 99, 102, 106. 60 keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Dengan demikian perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam hal ini peranan peraturan hukum sangat besar kaitannya dengan pelaksanaan peraturan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dapat diartikan pula bahwa keberhasilan atau kegagalan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya telah dimulai sejak peraturan hukum tersebut dibuat. Misalnya, badan legislatif atau instansi yang berwenang membuat peraturan tersebut telah membuat peraturan yang sulit dilaksanakan oleh masyarakat, sejak saat itulah awal kegagalan produk peraturan yang dibuat oleh badan tersebut. Hal ini dapat diakibatkan dalam peraturan tersebut memerintahkan sesuatu hal yang tidak didukung oleh sarana yang mencukupi, akibatnya, peraturan tersebut gagal untuk dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. 2.2. Pengertian Tindak Pidana dan Kekerasan dalam Rumah Tangga 1. Pengertian Tindak Pidana Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan tindak adalah perbuatan. Sedangkan pidana adalah kejahatan, kriminal. Jadi tindak pidana adalah suatu perbuatan yang jahat atau perbuatan kriminal. Barda Nawawi Arief menyatakan ” 61 tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.75 The term crime has no accepted definition in the law, except the circular one that is anything that the lawmakers define as a crime. Basically, a crime is a wrong, usually a moral wrong, committed againts the society as a whole. Criminal prosecutions are brought in order to punish wrongdoers, either because we want to deter future crime or simply because we believe wrongdoers deserve to be punished.76 Istilah tindak pidana tidak memiliki definisi dalam undang-undang yang berlaku, kecuali satu lingkaran yang adalah sesuatu bahwa pembuat undang-undang mendefinisikan sebagai suatu kejahatan. Pada dasarnya, kejahatan adalah sebuah kesalahan, biasanya kesalahan moral, yang bertentangan dengan masyarakat secara keseluruhan. Penuntutan pidana dilakukan untuk menghukum orang jahat, baik karena kita ingin mencegah kejahatan di masa depan atau hanya karena kita percaya orang jahat pantas untuk dihukum. Sudarto menyatakan ”tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (crime atau Verbrechen atau misdaad) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.77 Pengertian dan unsur-unsur tindak pidana ada dua golongan (pandangan) yaitu pandangan monistis dan dualistis. Menurut pandangan monistis bahwa keseluruhan adanya syarat pemidanaan merupakan sifat dari perbuatan, tidak ada pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Untuk lebih jelas mengenai tindak pidana (Stafbaar Feit) dan unsur-unsurnya berikut pendapat beberapa sarjana : 75 76 77 Barda Nawawi I, Op.cit, h. 73. Joshua Dressler, 1999, Criminal Law, Casenote Law Outlines, Santa Monica, CA, h. 3. Sudarto I, Op.cit, h. 40. 62 a. Simon berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggung jawab. b. Van Hamel berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, patut dipidana. c.Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan pidana. d. H.B. Vos berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah kelakuan manusia dan diancam pidana dalam undang-undang. e. Moeljatno dalam pidato dies natalis Universitas Gajah Mada memberi arti ”perbuatan pidana” sebagai ”perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. Untuk adanya perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum.78 Di dalam KUHP hanya ada asas legalitas (Pasal 1) yang merupakan “landasan yuridis” untuk menyatakan suatu perbuatan (feit) sebagai perbuatan yang dapat dipidana (strafbaarfeit). Namun apa yang dimaksud dengan “strafbaarfeit” tidak dijelaskan. Jadi tidak ada “pengertian/ batasan yuridis” tentang tindak pidana. Pengertian tindak pidana (strafbaarfeit) hanya ada dalam teori atau pendapat para sarjana. Dengan tidak adanya batasan yuridis, dalam praktik selalu diartikan bahwa “tindak pidana adalah suatu perbuatan yang telah dirumuskan dalam UU”. Hal ini didasarkan pada perumusan asas legalitas dalam 78 Ibid, h. 41-43. 63 Pasal 1 KUHP yang mengandung asas “nullum delictum sine lege” dan sekaligus mengandung asas “sifat melawan hukum yang formal”. Padahal secara teoritis dan menurut yurisprudensi serta menurut rasa keadilan, diakui adanya asas “tiada tindak pidana dan pemidanaan tanpa sifat melawan hukum (secara materiil)”. Asas ini sebenarnya juga tersimpul (secara implisit) di dalam “aturan khusus” KUHP, yaitu dengan adanya beberapa perumusan delik di Buku II yang secara eksplisit menyebutkan unsur melawan hukum (misalnya, Pasal 333 tentang Perampasan Kemerdekaan, Pasal 368 tentang Pemerasan, Pasal 406 tentang pengerusakan barang). Apabila unsur melawan hukum itu tidak ada / tidak terbukti, maka si pelaku tidak dapat dipidana, Ini berarti, ketentuan itu mengandung di dalamnya asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum” (no liability without unlawfulness). Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa unsur utama tindak pidana adalah perbuatan tersebut memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum. Tindak Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan. Yang terdiri dari : unsur Subjek, unsur kesalahan, unsur bersifat melawan hukum (dari tindakan yang bersangkutan), unsur tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh perundangan yang atas pelanggarannya diancamkan suatu pidana, dan unsur waktu, tempat dan keadaan. 2. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga 64 a. Pengertian Kekerasan Pemberian makna atas suatu konsep sangat tergantung pada norma dan nilai yang tumbuh, berkembang dan diakui dalam suatu masyarakat. Demikian pula halnya dengan tindak kekerasan, atau violence, pada dasarnya merupakan suatu konsep. Apapun bila dilihat dari bentuknya, tindak kekerasan mempunyai dampak yang sangat traumatis bagi perempuan, baik dikaitkan maupun tidak dengan kodrat perempuan itu sendiri. Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti :79 1) Perihal (yang bersifat, berciri) keras; 2) Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; 3) Paksaan. Bertolak belakang dari pengertian di atas, nampak bahwa kekerasan atau violence menunjuk kepada tingkah laku yang pertama harus bertentangan dengan undang-undang, tidak dibedakan dalam jenis-jenisnya secara khusus baik berupa ancaman saja maupun merupakan suatu tindakan nyata yang mengakibatkan kerusakan terhadap harta benda, fisik, atau menyebabkan kematian pada seseorang. Maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kekerasan, seperti layaknya terdapat dalam delik material. Violence dalam bahasa Inggris berarti kekerasan, kehebatan, kekejaman. Secara etimologi, kata “violence” merupakan gabungan dari kata 79 Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988, h. 425. 65 “vis” yang berarti daya atau kekuatan dan “latus” yang berasal dari kata “ferre” yang berarti membawa. Jadi, kekerasan adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan atau pun tekanan berupa fisik maupun non fisik80, atau dapat juga diartikan sebagai suatu serangan atau invasi fisik ataupun integritas mental psikologis seseorang. Seperti yang dikemukakan oleh Elizabeth Kandel Englander yang dikutip oleh Rika Saraswati, bahwa :81 “In general, violence is aggressive behavior with the intent to cause harm (physical or psychological). The word intent is central; physical or psychological harm that occurs by accident, in the absence of intent, is not violence.” Sedangkan pengertian kejahatan dengan kekerasan yang diberikan oleh B. Mardjono Reksodiputro sebagaimana dikutip oleh Sagung Putri, dapat diketahui bahwa dalam pengertian kejahatan kekerasan ada dua faktor penentu82 yaitu : a. Adanya penggunaan kekerasan, dan b. Adanya tujuan untuk mencapai tujuan pribadi yang bertentangan dengan orang lain. Berdasarkan Deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Kekerasan Terhadap Perempuan (1993), yang dimaksud dengan kekerasan 80 Romli Atmasasmita, 1988, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Eresco, Bandung, h. 55. 81 82 Rika Saraswati, 2006, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 13. Sagung Putri, M.E.Purwani, Viktimisasi Kriminal terhadap Perempuan, dalam Kerta Patrika, 2008, Vol. 33 No. 1, Januari, h. 3. 66 adalah :83 “Setiap tindakan yang berakibat atau memungkinkan berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, atau psikologis termasuk ancaman, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.” Pengertian kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu : “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.” Pingsan diartikan hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. kemudian, yang dimaksud dengan tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sama sekali, tetapi seseorang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui yang terjadi pada dirinya. Pengertian seperti itu tentulah akan membuat tujuan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak tercapai, bila digunakan sebagai tafsir kata kekerasan dalam UU PKDRT. Perbuatan kekerasan seperti tersebut di atas dapat dikatakan penganiayaan. Penganiayaan di dalam KUHP digolongkan menjadi dua, yaitu : penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 KUHP dan penganiayaan ringan dalam Pasal 352 KUHP. Pengertian penganiayaan berat adalah bila perbuatannya mengakibatkan luka berat, seperti yang diatur dalam Pasal 90 83 Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, 2004, Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, h. 66. 67 KUHP, luka berat dirumuskan sebagai jatuh sakit atau dapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggu daya pikir selama empat minggu, gugurnya/ mati kandungan seorang perempuan.84 Kekerasan terhadap perempuan yang ditemui pengaturannya dalam KUHP hanya meliputi kekerasan fisik saja dan belum meliputi kekerasan dalam bentuk lainnya. Selain membatasi pada jenis kekerasan secara fisik, KUHP juga membatasi kekerasan seksual terhadap perempuan hanya dapat dilakukan di luar perkawinan saja. Sehingga kekerasan seksual yang dilakukan terhadap perempuan yang terlibat dalam perkawinan, tidak dikriminalisasi sebagai suatu kejahatan dalam KUHP kecuali perempuan yang tersebut belum cukup umur untuk dikawini seperti yang diatur dalam Pasal 288 ayat (1) berikut : Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di dalam pernikahan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sebelum mampu dikawin, diancam, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, dengan pidana penjara paling lama empat tahun. 84 Rika Saraswati, Op.cit, h. 14. 68 Apabila Pasal ini dikaji ulang dengan merujuk pada Pasal 89 dimana akibat yang ditimbulkan adalah membuat korban pingsan atau lemah, Pasal 352 dan Pasal 354, maka seharusnya pada Pasal 288 ini pun bisa dijadikan dasar hukum kekerasan seksual dalam rumah tangga walaupun perbuatan “setubuh” dengan istri yang masih di bawah umur tersebut dilakukan dengan persetujuan istri tanpa paksaan mengingat adanya pengenaan pidana yang diperberat apabila perbuatan penganiayaan dilakukan terhadap ibu, bapak, istri, atau anaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 356 KUHP. Di sisi lain, seorang istri harus sadar akan kodratnya untuk selalu siap melayani suami walaupun dalam keadaan tidak siap. Artinya, istri wajib melayani suami sekali pun dalam keadaan terpaksa. Pengaturan pasal ini hanya diberlakukan terhadap suami apabila dilakukan terhadap istrinya yang masih di bawah umur. Lain halnya dengan undang-undang perkawinan yang tidak menyebutkan secara jelas yang dimaksud dengan kekerasan. Undang-undang perkawinan yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam penjelasannya Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan menyebutkan alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian salah satunya adalah bentuk kekerasan. Pasal 1 angka 11 Undnag-undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengartikan kekerasan sebagai : 69 Setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Ketentuan ini mengartikan kekerasan secara luas dalam segala bentuk atau cara dan kepada siapapun tanpa batasan. Menurut Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan85 adalah : Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenangwenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Mengenai batasan kekerasan terhadap perempuan yang termuat pada Pasal 1 Deklarasi tersebut tidak secara tegas disebutkan mengenai kekerasan dalam rumah tangga tetapi pada bagian akhir kalimat disebutkan “… atau dalam kehidupan pribadi”. Kehidupan pribadi dapat dimaksudkan sebagai kehidupan dalam rumah tangga. Rekomendasi Umum dari Konvensi Perempuan Nomor 19 memberikan penekanan untuk pentingnya menghapuskan kekerasan berbasis gender tersebut dengan menyebutkan : 85 Niken Savitri, 2008, HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP, Refika Aditama, Bandung, h. 47. 70 “… bahwa kekerasan berbasis gender adalah suatu bentuk diskriminasi yang merupakan hambatan serius bagi kemampuan perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-laki.”86 Rekomendasi tersebut juga secara resmi memperluas larangan atau diskriminasi berdasarkan gender dan merumuskan tindak kekerasan berbasis gender sebagai : “Tindak kekerasan yang secara langsung ditujuan kepada perempuan karena ia berjenis kelamin perempuan, atau mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional. Termasuk di dalamnya tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual, ancaman untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut, pemaksaan dan bentuk-bentuk perampasan kebebasan lainnya. R.Soesilo mengatakan :87 Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menerjang, dsb. Pengertian demikian lebih mendekati kepada maksud pembuat UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT, karena undang-undang ini telah mengkualifikasi perbuatan tersebut sedemikian rupa, sehingga sampai pada beberapa tingkatan. Dalam UU PKDRT kekerasan tersebut diatur secara bertingkat, mulai dari kekerasan tanpa mensyaratkan akibat apapun, sampai pada perbuatan yang menimbulkan akibat luka berat atau bahkan sampai mengakibatkan kematian korban. 86 87 Rekomendasi Umum CEDAW Nomor 19, dalam Sidang ke-11, tahun 1992. Soesilo R, 1981, KUHP dan Komentar, Politeia, Bogor, h. 84. 71 Secara ringkas, definisi kekerasan adalah setiap tindakan kekerasan verbal maupun fisik, pemaksaan atau ancaman pada nyawa yang dirasakan pada seseorang, apakah masih anak-anak atau sudah dewasa, yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis, penghinaan atau perampasan kebebasan seseorang. Sejumlah pengarang lain, misalnya Alan Weiner, Zahn dan Sagi mencoba merumuskan unsur-unsur kekerasan sebagai berikut: “…the threat, attempt, or use of physical force by one or more persons that results in physical or nonphysical harm to one or more other persons…”.88 Rumusan yang diberikan oleh para penulis di atas cenderung untuk memberikan titik berat pada physical force. Namun ada pula pendapat lain yang mengetengahkan bahwasannya kekerasan terhadap perempuan tidak hanya dibatasi pada physical force (kekerasan fisik), akan tetapi juga non-physical force (kekerasan non fisik) misalnya physicological force (kekerasan psikis), yang akibatnya tidak lebih ringan daripada penggunaan physical force. Cakupan yang sangat luas dari makna kekerasan yang diberikan dalam rumusan ini merupakan refleksi dari pengakuan atas realita sosial kekerasan terhadap perempuan yang terjadi selama ini di seluruh dunia. Bentuk-bentuk kekerasan yang tercakup didalamnya, oleh karenanya, merupakan kekerasan jasmani, seksual dan psikologis yang terjadi dalam rumah tangga, dalam masyarakat umum, dan juga yang dilakukan atau dibiarkan terjadinya oleh Negara. 88 Harkristuti Harkrisnowo, 2000, Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap Perempuan, KKCWPKWJ UI, Jakarta, h.79. 72 Dari pengertian di atas kekerasan terhadap perempuan dapat menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan, hal ini jelas melanggar hak asasi manusia. Dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa “hak wanita dalam undang-undang ini adalah hak asasi manusia” .89 Dengan demikian setiap pasal yang merupakan hak asasi manusia di undang-undang tersebut juga merupakan hak dari perempuan sebagai individu di dalam masyarakat. Perempuan memiliki hak untuk tidak menerima kekerasan dalam bentuk apapun yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Kekerasan terhadap perempuan, lebih spesifik lagi sering dikategorikan sebagai kekerasan berbasis gender. Hal ini disebabkan kekerasan terhadap perempuan seringkali diakibatkan adanya ketimpangan gender karena adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang. Hal ini antara lain dapat terefleksikan dari kekerasan dalam rumah tangga yang lebih sering dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan lebih kepada korban yang lebih lemah. Kekerasan berbasis gender ini memberikan penekanan khusus pada akar permasalahan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan, yaitu bahwa diantara pelaku dan korbannya terdapat relasi gender dimana dalam posisi dan perannya tersebut pelaku mengendalikan dan korban adalah orang yang dikendalikan melalui tindakan kekerasan tersebut.90 89 90 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Komnas Perempuan, 2006, Menyediakan Layanan Berbasis Komunitas. 73 Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun, yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan ketidakadilan baik bagi kaum lakilaki maupun terutama terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan gender terwujud dalam berbagai bentuk ketidakadilan, seperti marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak peenting dalam keputusan publik, pembentukan secara stereotip atau pelabelan negatif, kekerasan (violence), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (burden).91 Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender disebut juga dengan gender-related violence mempunyai macam dan bentuk kejahatan92, diantaranya : Pertama, bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk pemerkosaan di dalam perkawinan. Perkosaan terjadi jika seseorang melakukan paksaan untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan. Ketidakrelaan ini sering kali tidak bisa diungkapkan karena berbagai faktor, misalnya rasa malu, ketakutan, dan keterpaksaan, baik ekonomi maupun kultural. Kedua, tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga (domestic violence), termasuk tindak kekerasan dalam bentuk penyiksaan terhadap anak-anak (child abuse). Ketiga, bentuk penyiksaan yang mengarah pada organ vital kelamin (genital mutilation), misalnya penyunatan terhadap anak perempuan. Keempat, kekerasan dalam bentuk pelacuran (prostitution). Pelacuran merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh 91 92 Mansour Fakih, 1999, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 12. Ibid, h. 20. 74 suatu mekanisme ekonomi yang merugikan kaum perempuan. Setiap negara dan masyarakat selalu menggunakan standar ganda terhadap pekerja seksual ini. Di satu sisi, pemerintah melarang dan menangkap mereka, tetapi di lain pihak negara juga menarik pajak dari mereka. Selain itu, masyarakat selalu memandang rendah pelacur sebagai sampah masyarakat sementara tempat kegiatan mereka selalu ramai dikunjungi orang, terutama laki-laki. Kelima, kekerasan dalam bentuk pornografi. Pornografi termasuk kekerasan non fisik berupa pelecehan terhadap kaum perempuan karena tubuh perempuan dijadikan objek demi keuntungan seseorang. Keenam, kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam keluarga berencana (enforced sterilization). Keluarga berencana di banyak tempat ternyata telah menjadi sumber kekerasan terhadap perempuan. Dalam rangka memenuhi target mengontrol pertumbuhan penduduk, perempuan seringkali dijadikan korban demi program tersebut meskipun semua orang tahu bahwa persoalannya bukan saja pada perempuan, melainkan berasal dari kaun lakilaki juga. Ketujuh, kekerasan terselubung (molestation) berupa memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh. Jenis kekerasan ini sering terjadi di tempat pekerjaan atau di tempat umum. Kedelapan, tindakan kejahatan terhadap perempuan yang paling umum dilakukan masyarakat adalah pelecehan seksual. Banyak orang membela bahwa pelecehan seksual sangat relatif karena sering tindakan tersebut merupakan usaha untuk bersahabat, tetapi sesungguhnya pelecehan seksual bukanlah usaha untuk bersahabat karena tindakan tersebut merupakan hal tidak menyenangkan bagi perempuan. Ada beberapa penyebab yang menjadi asumsi terjadinya kekerasan terhadap perempuan93 : 93 Zaitunah Subhan, 2004, Kekerasan terhadap Perempuan, PT. Lkis Pelangi Aksara, Yogyakarta, h. 14-15. 75 1. Adanya persepsi tentang sesuatu dalam benak pelaku, bahkan seringkali yang mendasari tindak kekerasan ini bukan sesuatu yang dihadapi secara nyata. Hal ini dibuktikan dengan realitas di lapangan yang menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan tindakan kekerasan tersebut tanpa suatu alasan yang mendasar. Alasan yang disampaikan pelaku hampir selalu hanya didasarkan bahwa dirinya atau permainan bayang-bayang pikirannya saja, bahkan tidak jarang dia justru mengingkari telah berbuat jahat dan tidak terhormat. Lebih lagi jika pelaku menganggap tindakannya tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan mesum atau perkosaan misalnya. Sehingga ketika dihadap jaksa dia menolak tuduhan bahwa dia telah melakukan perkosaan. 2. Hukum yang mengatur tindak kekerasan terhadap perempuan masih bias gender. Seringkali hukum tidak berpihak kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan. Ketidakberpihakan tersebut tidak saja berkaitan dengan substansi hukum yang kurang memperhatikan kepentingan perempuan atau si korban, bahkan justru belum adanya substansi hukum yang mengatur nasib bagi korban kekerasan, yang umumnya dialami perempuan. Rika Saraswati melalui hasil penelitiannya di Rifka Annisa Women’s Crisis Centre Yogyakarta, bahwa terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena faktor gender dan patriarki, relasi kuasa yang timpang, dan role modeling (perilaku hasil meniru).94 Gender dan patriarki akan menimbulkan relasi kuasa yang tidak setara karena laki-laki dianggap lebih utama daripada perempuan berakibat pada kedudukan suami pun dianggap mempunyai kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya termasuk istri dan anak-anaknya. Anggapan bahwa istri milik suami dan seorang suami mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi daripada anggota keluarga yang lain menjadikan laki-laki berpeluang melakukan kekerasan. 94 Rika Saraswati, Op.cit, h. 20. 76 Sementara itu Aina Rumiati Azis menambahkan faktor cara pandang atau pemahaman terhadap agama yang dianut. Berikut faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan yang dikemukakan oleh Aina Rumiati Azis95 : Budaya patriarki yang mendudukan laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk interior. 1. 2. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama sehingga menganggap laki-laki boleh menguasai perempuan. 3. Peniruan anak laki-laki yang hidup bersama ayah yang suka memukul, biasanya akan meniru perilaku ayahnya. Realita kekerasan terhadap perempuan yang mengalami peningkatan setiap tahun mencapai titik yang mengkhawatirkan. Kekerasan terhadap perempuan paling banyak terjadi di rumah tangga dengan pelaku suami. Jika setiap lapisan masyarakat tidak berupaya memutus rantai kekerasan mulai dari sekarang dikhawatirkan hal ini akan merusak generasi penerus bangsa. Sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan setelah meratifikasi Konvensi mengenai Penghapusan Segala bentuk diskriminasi terhadap wanita melalui undang-undang No. 7 tahun 1984, pemerintah membentuk Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). 95 Aina Rumiati Aziz, 2002, Perempuan Korban di Ranah Domestik, www.indonesia.com, h. 2. 77 Terhadap jenis-jenis kekerasan, dalam Undang-undang PKDRT lebih diperluas lagi. Jenis-jenis kekerasan lain selain kekerasan fisik, ekonomi, dan seksual dapat ditemui pada Pasal 1 sebagai berikut : Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Namun lingkup pengaturan undang-undang tersebut hanya dalam cakupan domestik, yaitu mereka yang memiliki hubungan kekeluargaan atau berada dalam satu domisili yang sama, sehingga tidak dapat diberlakukan kepada korban perempuan pada umumnya yang tidak memenuhi kategori lingkup domestik tersebut. Dengan berlakunya undang-undang PKDRT, dalam pandangan yang progresif kiranya hakim dapat mempertimbangkan diaturnya jenis-jenis kekerasan tersebut di dalam Undang-undang PKDRT dari perspektif perlindungan terhadap korban kekerasan, sebagai salah satu acuan dalam memutus suatu perkara kekerasan terhadap perempuan. b. Kekerasan dalam Rumah Tangga Pengertian rumah tangga (keluarga) diambil pengertian keluarga yang luas, yang memasukkan juga orang tua dari ayah dan ibu, serta saudara-saudara yang tinggal dalam satu rumah. Hal ini disesuaikan dengan Pasal 356 KUHP, yang mengatur tentang penganiayaan dalam keluarga, yang juga ditujukan 78 kepada orang tua dari pelaku. Pengertian keluarga yang luas ini ditandaskan pula dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dengan menentukan, bahwa KDRT termasuk juga terhadap orang lain yang bekerja dan tinggal di rumah yang sama (dengan pelaku). Butir ke-6 Ulasan Umum Rekomendasi Umum Nomor 19 Tahun 1993 tentang Kekerasan terhadap Perempuan juga menegaskan bahwa : “Konvensi dalam Pasal 1, menetapkan definisi tentang diskriminasi terhadap perempuan. Definisi diskriminasi itu termasuk juga kekerasan berbasis gender, yaitu kekerasan yang langsung ditujukan kepada seorang perempuan, karena dia adalah perempuan atau hal-hal yang memberi akibat pada perempuan secara tidak proporsional. Hal tersebut termasuk tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual atau ancaman-ancaman seperti itu, paksaan dan perampasan kebebasan lainnya. Kekerasan berbasis gender bisa melanggar ketentuan tertentu dari Konvensi, walaupun ketentuan itu tidak secara spesifik tentang kekerasan”. Di Queensland Australia, menurut Domestic and Family Protection Act definisi kekerasan dalam rumah tangga adalah : Domestic violence is defined in state domestic violence protection legislation and includes personal injury, harassment, intimidation, indecency, and damage to property and threats of any of these behaviors. A further requirement of the definition is that the behavior must occur in the context of an intimate, spousal, family, or care relationship.96 Kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan dalam undang-undang perlindungan negara terhadap kekerasan domestik dan termasuk melukai orang, pelecehan, intimidasi, perbuatan keji, dan kerusakan harta benda dan ancaman dari setiap perilaku tersebut. Persyaratan lebih lanjut dari definisi ini 96 Heather Douglas and Tamara Walsh, 2010, Mothers, Domestic Violence, and Child Protection, University of Queensland, St Lucia, Queensland, Australia h. 491. 79 adalah bahwa perilaku tersebut harus terjadi dalam konteks suami, intim, keluarga, atau hubungan peduli. “All acts of genderbased physical and psychological abuse by a family member against women in the family, ranging from simple assault to aggravated physical battery, kidnapping, threats, intimidation, coercion, stalking, humiliating verbal abuse, forcible or unlawful entry, arson, destruction of property, sexual violence, marital rape, dowry or related violence, female genital mutiliation, violence through prostitution, against household workers and attempts to commit such acts shall be termed ‘domestic violence”.97 Semua tindakan berbasis gender baik fisik dan psikologis penyalahgunaan oleh anggota keluarga terhadap perempuan dalam keluarga, mulai dari serangan sederhana untuk memperburuk keadaan fisik, penculikan, ancaman, intimidasi, pemaksaan, menguntit, menyakiti dengan kata-kata/ verbal, masuk secara paksa atau perbuatan melanggar hukum, pembakaran, pengerusakan properti, kekerasan seksual, perkosaan dalam perkawinan, kekerasan mas kawin atau terkait, mutilasi kelamin perempuan, kekerasan melalui prostitusi, kekerasan terhadap pekerja rumah tangga dan upaya untuk melakukan tindakan tersebut disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebenarnya adalah : “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk 97 Rukmini Sen, 2010, Women’s Subjectivities of Suffering and Legal Rhetoric on Domestic Violence : Fissures in the two Discourses, SAGE Publications, New Delhi, h. 390. 80 melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.” Unsur-unsur yang dikandung dalam pengertian “kekerasan dalam rumah tangga/KDRT” praktis hampir sama dengan unsur-unsur dalam pengertian “kekerasan berbasis gender” dari Rekomendasi Umum Nomor 19 Tahun 1993, diantaranya : setiap perbuatan terhadap seseorang, dan dalam hal ini ditekankan pada terutama perempuan. Unsur lain yang diindikasi ada kesamaan, yakni mengenai bentuk kekerasan yang menimpa pada diri korban KDRT adalah adanya bentuk kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Sementara dalam pengertian kekerasan berbasis gender dalam Rekomendasi Umum Nomor 19 tersebut adalah unsur-unsur berupa tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual atau ancaman-ancaman seperti itu. Dalam perjalanannya, pengertian diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 CEDAW mengalami perkembangan yang cukup positif, hal mana bahwa bentuk kekerasan terhadap perempuan juga menjadi cakupan dalam pengertian diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini sebagaimana ditetapkan Komite CEDAW dalam Rekomendasi Umum Nomor 19 Tahun 1993 (Sidang ke-11, Tahun 1992) tentang Kekerasan terhadap Perempuan (Violence Against Women), diantaranya mengemukakan mengenai bentuk-bentuk diskriminasi yang menghalangi kaum perempuan dalam mendapatkan hak-hak kebebasannya yang setara dengan laki-laki 81 Ketentuan mengenai definisi “diskriminasi” dalam Pasal 1 CEDAW Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, dan pada Butir ke-6 Rekomendasi Umum Nomor 19 Tahun1993 serta Pasal 1 mengenai pengertian “kekerasan dalam rumah tangga” dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, nyata sekali bahwa hubungan satu dengan yang lain saling berkaitan, utamanya dalam menjabarkan arti diskriminasi, yang adalah termasuk juga bentuk kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan berbasis gender. Pasal 2 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menentukan lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi : a) suami, isteri, dan anak; b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian,yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Adapun pengertian kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana tertuang dalam rumusan pasal 1 Deklarasi Penghapusan Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan (istri) PBB dapat disarikan sebagai setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan 82 tertentu, pemaksaan atau perampasan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi (keluarga).98 Kemudian Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) menetapkan bahwa : “Dasar perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Hal ini berarti rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para anggotanya karena keluarga dibangun oleh suami istri atas dasar ikatan lahir batin diantara keduanya. Selain itu juga, menurut Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan bahwa : “Antara suami istri mempunyai kewajiban untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.” Bahkan suami dan istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup di dalam masyarakat serta berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Yang termasuk cakupan rumah tangga menurut Pasal 2 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah : 1) suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); 2) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana 98 disebutkan di atas karena hubungan darah, Deklarasi PBB, 2000, Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Kepada Perempuan, Washington DC, h. 2. 83 perkawinan (misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Asas Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam Pasal 3 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu : - Penghormatan hak asasi manusia; - Keadilan dan kesetaraan gender, yakni suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional. - Nondiskriminasi; dan - Perlindungan korban. Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga terutama digunakan untuk mengontrol seksualitas perempuan dan peran reproduksi mereka. Hal ini sebagaimana biasa terjadi dalam hubungan seksual antara suami dan istri di mana suami adalah pihak yang membutuhkan dan harus dipenuhi kebutuhannya, dan hal ini tidak terjadi sebaliknya. 84 Dalam konsideran deklarasi PBB juga dikatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah efek dari ketimpangan historis dari hubunganhubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi laki-laki atas perempuan. Dominasi ini terus dilanggengkan sehingga perempuan terus berada dalam ketertindasan. Budaya seperti inilah yang merupakan salah satu faktor awal munculnya peluang tindakan kekerasan terhadap perempuan (istri) dalam berbagai bentuknya. Dalam konteks Indonesia, kondisi dari budaya yang timpang sebagaimana disebutkan di atas telah menyebabkan hukum, dan sistem hukum (materiil hukum, aparat hukum, budaya hukum) yang ada kurang responsif dalam melindungi kepentingan perempuan. KUHAP sangat minim membicarakan hak dan kewajiban istri sebagai korban, ia hanya diposisikan sebagai saksi pelapor atau saksi korban. Begitu pula yang tercantum dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 31 ayat (3) : “Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.” Meski demikian, KUHP juga memuat peluang istri untuk mendapat keadilan. Kekerasan dan penganiayaan terhadap istri dalam KUHP merupakan tindak pidana yang sanksinya lebih besar sepertiga dari tindak pidana penganiayaan biasa atau dilakukan oleh dan terhadap orang lain, sebagaimana diterangkan dalam pasal 351 s.d. 355 KUHP. Pernyataan dalam KUHP tersebut dipertegas lagi dalam UU. No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada tanggal 22 September 2004 yang merupakan 85 hasil kerja cukup panjang dari berbagai elemen bangsa, baik dari pemerintah, parlemen, dan tentu saja masyarakat luas yang dalam hal ini diwakili oleh lembaga-lembaga yang mempunyai perhatian serius terhadap penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dan pembangunan hukum yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Adapun definisi kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 yaitu : “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.” Ratna Batara Munti menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat terjadi dalam berbagai bentuk sebagaimana diringkaskan di bawah ini yaitu :99 1) Kekerasan fisik langsung dalam bentuk pemukulan, pencakaran sampai pengrusakan vagina (kekerasan seksual) dan kekerasan fisik secara tidak langsung yang biasanya berupa memukul meja, membanting pintu, memecahkan piring, gelas, tempat bunga dan lain-lain, serta berlaku kasar. 2) Kekerasan psikologis, berupa ucapan kasar, jorok, dan yang berkonotasi meremehkan dan menghina, mendiamkan, menteror baik secara langsung maupun menggunakan media tertentu, berselingkuh, dan 99 Ratna Batara Munti, 2000, Advokasi Legislatif Untuk Perempuan: Sosialisasi Masalah dan Draft Rancangan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, LBH APIK, Jakarta, h. 36. 86 meninggalkan pergi tanpa kejelasan dalam waktu lama dan tanpa tanggung jawab. 3) Kekerasan ekonomi, berupa tidak diberikannya nafkah selama perkawinan atau membatasi nafkah secara sewenang-wenang, membiarkan atau bahkan memaksa istri bekerja keras, juga tidak memberi nafkah setelah terjadi perceraian meskipun pengadilan memutuskan. 4) Gabungan dari berbagai kekerasan sebagaimana disebutkan di atas baik fisik, psikologis, maupun ekonomis. Dengan mengacu pada Pasal 5 Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, maka kekerasan dalam rumah tangga dapat berwujud :100 1) Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit,atau luka berat; 2) Kekerasan Psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang; 3) Kekerasan seksual yang meliputi : pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu; 100 Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, 2009, Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya, h. 80. 87 4) Penelantaran rumah tangga, yaitu setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Termasuk dalam pengertian penelantaran adalah setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/ atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga yang cenderung terjadi adalah kekerasan fisik dan kekerasan seksual karena pembuktiannya lebih mudah yaitu berupa hasil visum. Selain itu yang sering juga mendapat pengaduan adalah adanya penelantaran dalam rumah tangga. Sedangkan pengaduan terhadap kekerasan psikis jarang terjadi karena pembuktian terhadap kekerasan psikis cukup sulit, tidak dapat terlihat dalam visum dan hanya dirasakan oleh korban saja. Dari keterangan tentang berbagai macam bentuk kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat diketahui bahwa kekerasan tersebut adalah suatu tindakan yang out of control yang dapat menjadi kebiasaan jahat yang dapat merugikan pasangan. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan yang dikemukakan oleh Aina Rumiati Azis101 : 1. Budaya patriarki yang mendudukkan laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk interior. 101 Aina Rumiati Aziz, 2002, Perempuan Korban di Ranah Domestik, www.indoesia.com, h. 2. 88 2. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama sehingga menganggap laki-laki boleh menguasai perempuan. 3. Peniruan anak laki-laki yang hidup bersama ayah yang suka memukul, biasanya akan meniru perilaku ayahnya. Fathul Djannah lebih memperinci faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut102 : Kemandirian ekonomi istri. Secara umum ketergantungan istri terhadap suami dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan, akan tetapi tidak sepenuhnya demikian karena kemandirian istri juga dapat menyebabkan istri menerima kekerasan oleh suami. 2. Karena pekerjaan istri. Istri bekerja di luar rumah dapat menyebabkan istri menjadi korban kekerasan. 3. Perselingkuhan suami. Perselingkuhan suami dengan perempuan lain atau suami kawin lagi dapat melakukan kekerasan terhadap istri. 4. Campur tangan pihak ketiga. Campur tangan anggota keluarga dari pihak suami, terutama ibu mertua dapat menyebabkan suami melakukan kekerasan terhadap istri. 5. Pemahaman yang salah terhadap ajaran agama. Pemahaman ajaran agama yang salah dapat menyebabkan timbulnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. 6. Karena kebiasaan suami, dimana suami melakukan kekerasan terhadap istri secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan 1. Adapun faktor dominan yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri adalah faktor ekonomi, dimana penghasilan istri lebih besar daripada suami. Hal ini menyebabkan sang istri menuntut banyak terhadap suami karena menganggap dirinya sebagai istri lebih mampu. Dalam hal ini istri yang adalah korban karena ketidak mampuannya mengendalikan kata-kata sehingga menyinggung suami juga berperan dalam terjadinya KDRT. Sehingga suami yang selalu mengalah akhirnya terpancing emosinya dan terjadilah kekerasan fisik terhadap istri. 102 Fathul Djannah, 2002, Kekerasan terhadap Istri, LKIS, Yogyakarta, h. 51. 89 Faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri telah diungkap dalam suatu penelitian yang oleh Istiadah diringkas sebagai berikut :103 1) Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri. Anggapan bahwa suami lebih berkuasa dari pada istri telah terkonstruk sedemikian rupa dalam keluarga dan kultur serta struktur masyarakat. Bahwa istri adalah milik suami oleh karena harus melaksanakan segala yang diinginkan oleh yang memiliki. Hal ini menyebabkan suami menjadi merasa berkuasa dan akhirnya bersikap sewenang-wenang terhadap istrinya. Jika sudah demikian halnya maka ketimpangan hubungan kekuasaan antara suami dan istri akan selalu menjadi akar dari perilaku keras dalam rumah tangga. 2) Ketergantungan ekonomi. Faktor ketergantungan istri dalam hal ekonomi kepada suami memaksa istri untuk menuruti semua keinginan suami meskipun ia merasa menderita. Bahkan, sekalipun tindakan keras dilakukan kepadanya ia tetap enggan untuk melaporkan penderitaannya dengan pertimbangan demi kelangsungan hidup dirinya dan pendidikan anak-anaknya. Hal ini dimanfaatkan oleh suami untuk bertindak sewenang-wenang kepada istrinya. 3) Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik. Faktor ini merupakan faktor dominan ketiga dari kasus kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya kekerasan ini dilakukan sebagai pelampiasan dari ketersinggungan, ataupun kekecewaan karena tidak dipenuhinya keinginan, kemudian dilakukan tindakan kekerasan dengan tujuan istri dapat memenuhi keinginannya dan tidak melakukan perlawanan. Hal ini didasari oleh anggapan bahwa jika perempuan rewel maka harus diperlakukan secara keras agar ia menjadi penurut. Anggapan di atas membuktikan bahwa suami sering menggunakan kelebihan fisiknya dalam menyelesaikan problem rumah tangganya. 4) Persaingan Jika di muka telah diterangkan mengenai faktor pertama kekerasan dalam rumah tangga adalah ketimpangan hubungan kekuasaan antara suami dan istri. Maka di sisi lain, perimbangan antara suami dan istri, baik dalam hal pendidikan, pergaulan, penguasaan ekonomi baik yang mereka alami sejak masih kuliah, di lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal, dapat menimbulkan persaingan dan selanjutnya dapat menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Bahwa di satu sisi suami tidak mau kalah, sementara di sisi lain istri juga tidak mau terbelakang dan dikekang. 103 Istiadah, Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam, Lembaga Kajian Agama Dan Jender dengan PSP, Jakarta, h. 18. 90 5) Frustasi Terkadang pula suami melakukan kekerasan terhadap istrinya karena merasa frutasi tidak bisa melakukan sesuatu yang semestinya menjadi tanggung jawabnya. Hal ini biasa terjadi pada pasangan yang : belum siap kawin, suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang mencukupi kebutuhan rumah tangga, masih serba terbatas dalam kebebasan karena masih menumpang pada orang tua atau mertua. Dalam kasus ini biasanya suami mencari pelarian kepada mabuk-mabukan dan perbuatan negatif lain yang berujung pada pelampiasan terhadap istrinya dengan memarahinya, memukulnya, membentaknya dan tindakan lain yang semacamnya. 6) Kesempatan yang kurang bagi perempuan dalam proses hukum Pembicaraan tentang proses hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak terlepas dari pembicaraan hak dan kewajiban suami istri. Hal ini penting karena bisa jadi laporan korban kepada aparat hukum dianggap bukan sebagai tindakan kriminal tapi hanya kesalahpahaman dalam keluarga. Hal ini juga terlihat dari minimnya KUHAP membicarakan mengenai hak dan kewajiban istri sebagai korban, karena posisi dia hanya sebagai saksi pelapor atau saksi korban. Dalam proses sidang pengadilan, sangat minim kesempatan istri untuk mengungkapkan kekerasan yang ia alami. Dengan demikian faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dapat disebabkan oleh adanya berbagai faktor baik faktor dari luar atau lingkungan dan juga adanya faktor dari dalam diri pelaku sendiri. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya. Faktor lingkungan lain seperti stereotype bahwa lakilaki adalah tokoh yang dominan, tegar dan agresif. Adapun perempuan harus bertindak pasif, lemah lembut dan mengalah. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami. Kebanyakan istri berusaha 91 menyembunyikan masalah kekerasan dalam keluarganya karena merasa malu pada lingkungan sosial dan tidak ingin dianggap gagal dalam berumah tangga. Dari beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga seperti yang telah disebutkan di atas faktor yang paling dominan adalah budaya patriarki dimana kedudukan laki-laki dianggap lebih tinggi dari kedudukan perempuan. Budaya patriarki ini mempengaruhi budaya hukum masyarakat. c. Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Arif Gosita mengemukakan bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang menderita. Mereka di sini dapat berarti : individu, atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.104 Berkenaan dengan korban, Kindern sebagaimana dikutip Mulyana W. Kusumah, mengemukakan : Salah satu kesulitan utama yang dihadapi di dalam merumuskan mengenai apa arti “korban” berasal dari perluasan tingkat pendekatan viktimologi atas bentuk-bentuk kejahatan dan delikuensi. Sebagai akibatnya, pertanyaan yang timbul adalah sejauh mana pengertian korban, dapat secara beralasan diterapkan pada kasus dimana tidak terdapat penderitaan badan, kehilangan atau rusaknya hak milik atau juga ancaman terhadap seseorang harus pasti bahwa korban benar-benar mengalami derita fisik atau psikologis atau bahwa bentuk-bentuk kerugian tertentu telah dilakukan atas korban secara pribadi atau bukan.105 104 105 Arif Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Edisi Kedua, Akademika Pressindo, Jakarta, h. 63. Mulyana W. Kusumah, 1984, Kriminologi dan Masalah Kejahatan, Armico, Bandung, h. 109. 92 Dari apa yang dikemukakan Kinden Nampak bahwa untuk sampai pada pemberian batasan korban, diperlukan adanya suatu kriteria yang harus dipenuhi. Hal ini tentunya dapat diterima, karena kondisi konotasinya dapat mengarah pada “crime without victim” atau kejahatan tanpa korban. Korban (victim) adalah “… whose pin and suffering have been neglected by the state while it spends immense resources to hunt down and punish the offender who responsible for that pain and suffering”.106 Di sini, pengertian korban lebih ditekankan pada kelalaian negara terhadap korban. Dari beberapa definisi korban tersebut di atas, yang perlu dicermati adalah bahwa korban yang dimaksud adalah hanya seorang korban yang secara langsung mengalami tindak pidana. Padahal sangat memungkinkan sekali atas suatu tindak pidana tersebut dampak yang dirasakan meluas, tidak hanya oleh korban yang secara langsung mengalami tindak pidana bahkan dampak tindak pidana tersebut juga dirasakan oleh ahli warisnya apalagi korban tidak punya hubungan darah dengan pelaku. Ada 5 (lima) tipologi korban menurut Sellin dan Wolfgang107, yaitu : Primary victimization : yang dimaksud di sini adalah korban individual dan bukan kelompok; 2. Secondary victimization : yang menjadi korban adalah kelompok atau pun badan hukum; 3. Tertiary victimization : yang menjadi korban adalah masyarakat luas; 4. Mutual victimization : yang menjadi korban adalah pelaku sendiri, misalnya dalam praktek pelacuran, perjudian atau pun perzinahan; dan 1. 106 107 Romli Atmasasmita, 1999, Masalah Santunan Korban Kejahatan, BPHN, Jakarta, h. 9. Barda Nawawi Arief, 1998, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, (Selanjutnya disebut Barda Nawawi III), h. 16. 93 No victimization, di sini bukan berarti tidak ada koban, tetapi korban tidak segera dapat diketahui. Misalnya dalam tindak pidana penipuan konsumen. 5. Perkembangan ilmu viktimologi selain mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan posisi korban juga memilah-milah jenis korban hingga kemudian muncullah berbagai jenis korban, yaitu sebagai berikut : Nonparticipating victims, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan. b. Latent victims, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban. c. Provocative victims, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan. d. Participating victims, yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban. e. False victims, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.108 a. Tipologi korban sebagaimana dikemukakan di atas, memiliki kemiripan dengan tipologi yang oleh Schafer diidentifikasi menurut keadaan dan status korban109, yaitu sebagai berikut : a. Unrelated victims, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama b. c. d. e. f. 108 109 sekali dengan pelaku, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam kasus ini tanggung jawab sepenuhnya terletak pada pelaku. Provocative victims, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya pada kasus selingkuh, dimana korban juga sebagai pelaku. Participating victims, yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban. Biologically weak victims, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban. Socially weak victims, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban. Self victimizing victims, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, misalnya korban obat bius. judi, aborsi, prostitusi. Muladi, 2005, HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Refika Aditama, Bandung, h. 42. Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2004, Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam, Cetakan Pertama, Ghalia Press, Jakarta, h. 42. 94 Berkaitan dengan korban kejahatan ini John A. Mack menulis ada tiga tipologi keadaan sosial dimana seseorang dapat menjadi korban kejahatan110, yaitu : - Calon korban sama sekali tidak mengetahui akan terjadi kejahatan, ia sama sekali tidak ingin jadi korban bahkan selalu berjaga-jaga atau waspada terhadap kemungkinan terjadi kejahatan. - Calon korban tidak ingin, menjadi korban, tetapi tingkah laku korban atau gerak-geriknya seolah-olah menyetujui untuk menjadi korban. - Calon korban tahu ada kemungkinan terjadi kejahatan, dan ia sendiri tidak ingin jadi korban tetapi tingkah laku seolah-olah menunjukkan persetujuannya untuk menjadi korban. Pandangan-pandangan tersebut menunjukkan bahwa kajian terhadap korban masih terbatas pada interaksi antara korban dan pelaku, yaitu sampai seberapa jauh korban mempengaruhi pelaku untuk melakukan kejahatan atau sampai seberapa jauh pelaku kejahatan memanfaatkan kelemahan korban. Sehubungan dengan definisi korban, terkait dengan penelitian ini penulis lebih menitikberatkan pada perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga karena kelemahannya sebagai perempuan (Biologically weak victims) mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 27 tahun 2004, ataupun penelantaran istilah yang digunakan dalam undangundang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dan bahkan karena status sosialnya yang lebih rendah (Socially weak victims), perempuan rentan mengalami tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. 110 Sagung Putri M.E. Purwani, Op.cit, h. 4. 95 Hasil penelitian Rifka Anissa Women’s Crisis Center menyebutkan bahwa ternyata baik perempuan (istri) sebagai korban, maupun laki-laki (suami) sebagai pelaku, mempunyai karakteristik tertentu. Karakteristik perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut111 : 1. Mempunyai penghargaan terhadap diri sendiri (self esteem) yang rendah, sehingga cenderung pasrah, mengalah. 2. Percaya pada semua mitos yang “memaklumi sikap kasar” suami pada istri. 3. Tradisionalis; percaya pada keutuhan keluarga, Stereotype Feminine. 4. Merasa bertanggung jawab atas kelakuan suaminya. 5. Merasa bersalah, menyangkut terror dan kemarahan yang dirasakan. 6. Berwajah tidak berdaya, tetapi sangat kuat dalam menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. 7. Stres yang dideritanya menimbulkan keluhan fisik tertentu (sakit kepala, gangguan pencernaan, dan sebagainya). 8. Menggunakan seks sebagai cara untuk membina kelangsungan hubungan dengan suami. 9. Diperlakukan seperti “anak kecil ayah” (pantas untuk dimarahi, dihukum dan sebagainya). 10. Yakin bahwa tidak ada orang lain yang mampu menolong penderitaannya. Setelah mengetahui karakteristik pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga, maka bisa dimaklumi bahwa untuk mengungkap masalah kekerasan dalam rumah tangga, sangat sulit. Apalagi korban yaitu para istri yang mengalami penderitaan tersebut menyerah pada apa yang dialaminya. Oleh karena itu, partisipasi perempuan (istri) sangat diharapkan dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. Banyak faktor yang menyebabkan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak melaporkan penderitaan yang menimpanya, antara lain :112 111 112 Moerti Hadiati Ssoeroso, 2010, Kekerasan dalam Rumah Tangga (dalam perspektif Yuridis-Viktimologis), Sinar Grafika, Jakarta, h. 84-85. Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, Op.cit, h. 81. 96 1) Si pelaku dengan si korban memiliki hubungan keluarga atau hubungan karena perkawinan. Hal ini biasanya menyulitkan karena keengganan korban untuk melaporkan mengenai apa yang telah terjadi kepada mereka. Pemikiran yang juga ikut mendasari alasan ini adalah rasa takut pada diri si korban karena si pelaku biasanya tinggal satu atap dengan mereka sehingga apabila korban mengadukan apa yang telah terjadi kepadanya pada pihak yang berwajib, si korban akan mendapatkan perlakuan yang lebih parah dari si pelaku ketika korban pulang atau ketika mereka bertemu kembali. 2) Keengganan korban mengadukan kekerasan yang telah menimpanya dapat juga disebabkan masih dipertahankannya pola pikir bahwa apa yang terjadi di dalam keluarga, sekalipun itu perbuatanperbuatan kekerasan, sepenuhnya merupakan permasalahan rumah tangga pribadi. Dengan demikian, melaporkan hal tersebut atau bahkan hanya membicarakannya saja, sudah dianggap membuka aib keluarga. 3) Kurang percayanya masyarakat kepada sistem hukum Indonesia sehingga mereka tidak memiliki pegangan atau kepastian hukum bahwa mereka akan berhasil keluar dari cengkeraman si pelaku. Menurut Harkristuti Harkrisnowo, adanya non-reporting of crime dalam kasus tindak kekerasan merupakan suatu fenomena universal, yang dijumpai juga di negara-negara lain. Adanya non-reporting ini disebabkan beberapa hal, berikut :113 1) Si korban malu karena peristiwa ini telah mencemarkan dirinya, baik secara fisik, psikologis maupun sosiologis. 2) Si korban merasa berkewajiban melindungi nama baik keluarganya, terutama jika pelaku adalah anggota keluarga sendiri. 3) Si korban merasa bahwa proses peradilan pidana terhadap kasus ini belum tentu dapat membuat dipidananya pelaku. 4) Si korban khawatir bahwa diprosesnya kasus ini akan membawa cemar yang lebih tinggi lagi pada dirinya (misalnya melalui publikasi media massa, atau cara pemeriksaan aparat hukum yang dirasanya membuat makin terluka). 5) Si korban khawatir akan retaliasi atau pembalasan dari pelaku (terutama jika pelaku adalah orang yang dekat dengan dirinya). 6) Lokasi kantor polisi yang jauh dari tempat tinggal korban, membuatnya enggan melapor. 7) Keyakinan korban bahwa walaupun ia melapor ia tidak akan mendapat perlindungan khusus dari penegak hukum. 113 Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, Op.cit, h. 82. 97 8) Ketaktahuan korban bahwa yang dilakukan terhadap dirinya merupakan suatu bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan. Setelah keluarnya Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diundangkan pada 22 September tahun 2004, muncul kesadaran dari korban untuk melaporkan ke pihak berwajib apabila terjadi aksi kekerasan dalam rumah tangga. Karena kekerasan sebagaimana tersebut di atas terjadi dalam rumah tangga, maka penderitaan akibat kekerasan ini tidak hanya dialami oleh istri saja tetapi juga anak-anaknya. Adapun dampak kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa istri adalah :114 1) Kekerasan fisik langsung atau tidak langsung dapat mengakibatkan istri menderita rasa sakit fisik dikarenakan luka sebagai akibat tindakan kekerasan tersebut. 2) Kekerasan seksual dapat mengakibatkan turun atau bahkan hilangnya gairah seks, karena istri menjadi ketakutan dan tidak bisa merespon secara normal ajakan berhubungan seks. 3) Kekerasan psikologis dapat berdampak istri merasa tertekan, shock, trauma, rasa takut, marah, emosi tinggi dan meledak-ledak, kuper, serta depresi yang mendalam. 4) Kekerasan ekonomi mengakibatkan terbatasinya pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang diperlukan istri dan anak-anaknya. Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa kekerasan tersebut juga dapat berdampak pada anak-anak. Adapun dampak-dampak itu dapat berupa efek 114 Ratna Batara Munti, loc. cit. 98 yang secara langsung dirasakan oleh anak, sehubungan dengan kekerasan yang ia lihat terjadi pada ibunya, maupun secara tidak langsung. Bahkan, sebagian dari anak yang hidup di tengah keluarga seperti ini juga diperlakukan secara keras dan kasar karena kehadiran anak terkadang bukan meredam sikap suami tetapi malah sebaliknya. Kekerasan dalam rumah tangga yang anak lihat adalah sebagai pelajaran dan proses sosialisasi bagi dia sehingga tumbuh pemahaman dalam dirinya bahwa kekerasan dan penganiayaan adalah hal yang wajar dalam sebuah kehidupan berkeluarga. Pemahaman seperti ini mengakibatkan anak berpendirian bahwa : satu-satunya jalan menghadapi stres dari berbagai masalah adalah dengan melakukan kekerasan, tidak perlu menghormati perempuan, menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan berbagai persoalan adalah baik dan wajar, menggunakan paksaan fisik untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan adalah wajar dan baik-baik saja. Di samping dampak secara langsung terhadap fisik dan psikologis sebagaimana disebutkan, masih ada lagi akibat lain berupa hubungan negatif dengan lingkungan yang harus ditanggung anak. Ketidakpedulian masyarakat dan negara terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga karena adanya ideologi gender dan budaya patriarki. Gender adalah pembedaan peran sosial dan karakteristik laki-laki dan perempuan yang dihubungkan atas jenis kelamin mereka. Pengertian patriarki adalah budaya yang menempatkan laki-laki sebagai yang utama atau superior dibandingkan dengan perempuan. Ideologi gender dan budaya patriarki kemudian oleh pemerintah dilegitimasi disemua aspek kehidupan. Hal-hal yang 99 berkaitan dengan bidang domestik, seperti rumah tangga dan reproduksi dikategorikan privat dan bersifat personal, misalnya relasi suami istri, keluarga, dan seksualitas. Hal-hal yang berada di luar campur tangan masyarakat/ individu lain dan negara. Akibat budaya patriarki dan ideologi gender tersebut berpengaruh juga terhadap ketentuan di dalam Undang-Undang Perkawinan yang membedakan laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga yang menimbulkan pandangan dalam masyarakat seolah-olah kekuasaan laki-laki sebagai suami sangat besar sehingga dapat memaksakan semua kehendaknya, termasuk melalui kekerasan. Kondisi tersebut menimbulkan akibat kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan yang terjadi di dalam ruang lingkup privat/ domestik ini menjadi tindakan yang tidak dapat dijangkau oleh negara. Tindakan-tindakan yang melanggar hak perempuan dan seharusnya menjadi tanggung jawab negara dan aparat, justru disingkirkan untuk menjadi urusan keluarga. Upaya untuk mengatur kekerasan dalam rumah tangga ke dalam suatu perundang-undangan telah dilakukan melalui Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undangundang tersebut merupakan tuntutan masyarakat yang telah sesuai dengan tujuan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 untuk menghapus segala bentuk kekerasan di Indonesia, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu juga, sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan. Dengan 100 demikian, terlihat ada perubahan pandangan dari pemerintah mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, tidak semata-mata merupakan urusan privat, tetapi juga menjadi masalah publik, dari urusan rumah tangga menjadi urusan publik yang diatur melalui Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). BAB III KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MERUMUSKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 3.1. Latar Belakang dan Tujuan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dikeluarkannya Undang-Undang Induk peraturan hukum pidana positif Indonesia adalah Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP). pandangan yang menganggap semua masalah kejahatan harus diatur dalam suatu kodifikasi hukum seperti KUHP atau KUHAP adalah pandangan yang sempit dan ketinggalan zaman serta tidak sesuai dengan tuntutan yang ada. Karena pada era modernisasi dimana pembagian kerja semakin kompleks, kebutuhan akan adanya peraturan-peraturan khusus yang bisa menjangkau permasalahan di lapangan semakin mendesak untuk segera 101 diakomodir. Masalah kekerasan dalam rumah tangga perlu diatur secara khusus dalam sebuah UU, mengingat konteks permasalahannya yang juga spesifik. Pentingnya keberadaan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat dijelaskan dalam prinsip hukum yakni berpegang pada adagium lex priori yaitu : hukum atau aturan yang baru mengalahkan hukum atau aturan yang lama, dan lex spesialis derogat legi generalis yaitu : hukum atau aturan yang bersifat khusus mengalahkan hukum atau aturan yang bersifat umum. Telah kita kenal dalam ilmu hukum pidana sebuah pembagian pidana sebagai berikut : a. Pidana umum, yaitu sebuah pidana yang berlaku umum sebagaimana yang telah diatar dalam KUHP, beserta semua perundangundangan yang mengubah dan menambah KUHP itu sendiri. b. Pidana khusus, yaitu pidana yang tidak diatur dalam pidana umum (KUHP), atau perundang-undangan yang berada diluar KUHP yang bersanksi pidana, beserta perundang-undangan yang mengubah dan menambahnya. Dari pembagian tindak pidana diatas dapat diketahui bahwa tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini merupakan tindak pidana khusus dan mempunyai undang-udang tersendiri. Domestic violence is the most common violent crime reported to police and typically involves a male perpetrator and a female victim the domestic violence victims who sought help at some point had sought assistance through the criminal justice system. Women’s rights activists have advocated that batterers be arrested, prosecuted, and sentenced in the same manner as other violent offenders.115 115 Lois A. Ventura Gabrielle davis, 2005, Domestic Violence Court Case Conviction and Recidivism, University of Toledo, Amerika Serikat, h. 255. 102 Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan kekerasan yang paling umum dilaporkan ke polisi dan biasanya melibatkan pelaku laki-laki dan perempuan sebagai korban. Korban kekerasan dalam rumah tangga telah meminta bantuan melalui sistem peradilan pidana. Aktivis hak-hak perempuan telah menganjurkan bahwa pelaku harus ditangkap, dituntut, dan dihukum dengan cara yang sama seperti pelaku kekerasan lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga sudah merupakan perbuatan yang perlu dikriminalisasikan karena secara substansi telah melanggar hak-hak dasar atau fundamental yang harus dipenuhi negara seperti tercantum dalam pasal 28 amandemen UUD 1945, Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againsts Women), dan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tanggal 22 September 2004 bisa jadi merupakan tanggal bersejarah bagi kalangan feminis di Indonesia. Setidaknya, satu dari sekian banyak agenda perjuangan mereka yang terkait dengan isu perempuan, yakni upaya pencegahan dan penghapusan (isu) Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah dan DPR RI akhirnya sepakat untuk mengesahkan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau dikenal dengan UU KDRT. Adanya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjadi penting, karena Undang-Undang tersebut mencantumkan 103 mekanisme yang didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan korban, yang pokok-pokoknya, sebagai berikut : 1. Kewajiban masyarakat dan negara untuk melindungi korban 2. Perintah perlindungan terhadap korban serta perintah pembatasan gerak sementara terhadap pelaku 3. Bantuan hukum bagi korban 4. Perlindungan saksi 5. Prosedur alternatif pengajuan tuntutan 6. Prosedur pembuktian yang tidak mempersulit korban, kesaksian korban dapat dipakai dan diperkuat oleh keterangan ahli maka perkara bisa terus diajukan hingga ke penuntutan 7. Alat pembuktian menerapkan pula visum psikiatrikum 8. Penanganan secara integratif / terpadu dari instansi hukum, instansi medis atau instansi pemerintah lainnya dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan. 1. Latar Belakang dikeluarkannya Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga Masalah kekerasan dalam rumah tangga pertama kali dibahas dalam seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1991. Materi seminar difokuskan pada suatu wacana adanya tindak kekerasan yang luput dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum, yaitu tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Dalam seminar tersebut diusulkan pembentukan undang-undang khusus untuk 104 menanggulangi tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Ada yang menyetujui dibentuknya undang-undang khusus, tetapi ada juga yang menentangnya. Dengan alasan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah cukup mengaturnya. Baik yang pro maupun yang kontra terhadap dibentuknya undang-undang baru tersebut, memberikan argumentasi menurut sudut pandang masing-masing. Namun, kiranya perjuangan kaum perempuan dan sebagian kaum laki-laki yang mengikuti seminar tersebut tidak berhenti sampai di situ. Karena sejak itu kaum perempuan mulai bangkit dengan berbagai upaya untuk menyingkap tradisi yang mengharuskan perempuan menutupi tindakan kekerasan dalam keluarga. Kekerasan terhadap perempuan (baik yang terjadi dalam rumah tangga maupun dalam lingkungan kehidupan bernegara dan bermasyarakat lainnya) bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan prinsip kesetaraan jender. Diskriminasi terhadap perempuan sudah lama ditentang oleh masyarakat internasional dengan adanya Convention on the Elimination of Discrimination of All Forms against Women tahun 1978 (CEDAW). Konvensi ini sudah diratifikasi oleh pemerintah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984. Dengan diratifikasinya konvensi tersebut, maka menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk mentransformasikan ketentuan yang ada dalam konvensi tersebut ke dalam hukum nasional. Salah satu perwujudan aturan dalam konvensi CEDAW ke dalam sistem hukum nasional kita adalah diberlakukannya Undangundang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya ditulis UU PKDRT). Latar belakang diberlakukannya 105 undang-undang ini adalah sebagaimana dapat dibaca dalam bagian menimbang dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004, yang antara lain menyatakan : “Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus” Sebelum adanya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), KDRT selalu diindikasikan sebagai salah satu bentuk delik aduan. Padahal sebenarnya apabila dilihat dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP (tentang Penganiayaan) dan Pasal 356 KUHP (Pemberatan) sama sekali tidak mensyaratkan adanya satu delik aduan. Hanya saja masyarakat (khususnya aparat penegak hukum) selalu meganggap jika suatu kasus berkaitan dengan keluarga maka selalu dinyatakan sebagai delik aduan, padahal kasus itu sebenarnya adalah sebuah kejahatan murni. Kalaupun misalnya dibelakang hari nanti korban melakukan pencabutan aduan, seharusnya polisi bersikap tegas dengan menganggap bahwa apa yang dilaporkan itu memang sebagai bentuk kejahatan dan harus ditindaklanjuti ke pengadilan. Hal ini memang menjadi kendala yang sangat umum sekali dalam persoalan KDRT, karena kelompok korban memang tidak bisa menyatakan secara berani bahwa ini adalah sebuah kejahatan yang harus ditindaklanjuti dengan proses hukum. ketidakberanian korban sangat berkaitan erat dengan budaya yang berlaku di Indonesia, yaitu budaya patriarki yang sangat kental yang serigkali melihat bahwa masalah KDRT bisa diselesaikan tanpa melalui jalur hukum. Ironisnya, pilihan untuk meyelesaikan persoalan KDRT tanpa melalui jalur hukum selalu disampaikan oleh aparat penegak hukum 106 sendiri. Padahal aparat penegak hukum sebetulnya sangat mengetahui bahwa persoalan KDRT adalah kejahatan yang harus direspon dengan hukum. KDRT memang tidak bisa dilepaskan secara murni sebagai satu bentuk kejahatan tanpa harus disandingkan dengan satu bentuk hubungan keluarga. Hal itu merupakan hal yang sangat dilematis dan hal itu juga disadari oleh korban, khususnya oleh istri yang biasanya sebagai korban. Umumnya para korban tersebut memilih melakukan gugatan karena dianggapnya sebagai jalur yang tidak berkonflik dibandingkan dengan jalur pidana yang dampaknya lebih jauh (pelaku/ suami korban kemungkinan akan dipidana penjara). Oleh karena itu adanya Undang-Undang yang mengatur KDRT sangat didukung oleh berbagai pihak. Pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar pikiran pengajuan UndangUndang Kekerasan dalam Rumah Tangga tersebut adalah sebagai berikut: a. Kasus kekerasan dalam rumah tangga makin menunjukkan peningkatan yang signifikan dari hari ke hari, baik kekerasan dalam bentuk kekerasan fisik atau psikologis maupun kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Bahkan, sudah menjurus dalam bentuk tindak pidana penganiayaan dan ancaman kepada korban, yang dapat menimbulkan rasa ketakutan atau penderitaan psikis berat bahkan kegilaan pada seseorang; b. Pandangan yang berpendapat semua kejahatan harus diatur dalam suatu kodifikasi hukum, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pandangan yang tidak mendukung adanya pembaruan hukum sesuai dengan tuntutan 107 perkembangan yang ada, karena peraturan perundang-undangan tersebut belum menyentuh permasalahan yang mendasar; c. Para korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami berbagai hambatan untuk dapat mengakses hukum seperti sulit untuk melaporkan kasusnya ataupun tidak mendapat tanggapan positif dari aparat penegak hukum; d. Ketentuan Hukum Acara Pidana atau perundang-undangan lainnya sejauh ini terbukti tidak mampu memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Selama ini, masyarakat masih menganggap kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada lingkup keluarganya sebagai persoalan pribadi yang tidak boleh dimasuki pihak luar. Bahkan sebagian masyarakat termasuk perempuan yang menjadi korban ada yang menganggap kasus-kasus tersebut bukan sebagai tindak kekerasan, akibat masih kuatnya budaya patriarki di tengah-tengah masyarakat yang selalu mensubordinasi dan memberikan pencitraan negatif terhadap perempuan sebagai pihak yang memang 'layak' dikorbankan dan dipandang sebatas "alas kaki di waktu siang dan alas tidur di waktu malam". Di sisi lain, kalangan feminis juga memandang bahwa produk-produk hukum yang ada semisal KUHP dan rancangan perubahannya, UU Perkawinan dan rancangan amandemennya, UU Pornografi dan Pornoaksi, dan lain-lain-sejak awal memang tidak dirancang untuk mengakomodasi kepentingan perempuan, melainkan hanya untuk memihak dan melindungi nilai-nilai moralitas dan positivisme saja. Sebagai contoh, sebelum adanya UU Penghapusan KDRT ketentuan hukum yang ada 108 masih memasukkan kasus kekerasan terhadap perempuan seperti kasus perkosaan, perdagangan perempuan, dan kasus pornografisme sebagai persoalan kesusilaan, bukan dalam kerangka melindungi integritas tubuh perempuan yang justru sering menjadi korban. Implikasinya, selain memunculkan rasa ketidakadilan dalam hukum, kondisi ini juga tak jarang malah menempatkan perempuan yang menjadi korban sebagai pelaku kejahatan atau memberinya celah untuk mengalami kekerasan berlipat ganda. Wajar jika pada tataran tertentu, hukum-hukum tersebut justru dianggap sebagai pengukuh marjinalisasi perempuan, yang meniscayakan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk KDRT, terus berlangsung tanpa bisa 'tersentuh' oleh hukum. Fakta-fakta inilah yang menginspirasi kalangan feminis sehingga mereka merasa perlu melakukan pembaruan institusional dan hukum yang lebih memihak kepada perempuan melalui langkah-langkah yang strategis dan sistematis. Pembaruan institusional yang mereka maksud adalah upaya-upaya mengubah pola budaya yang merendahkan perempuan, termasuk melalui kurikulum pendidikan, seraya menutup peluang penggunaan tradisi, norma, dan tafsiran agama untuk menghindari kewajiban memberantasnya. Adapun pembaruan hukum diarahkan untuk menciptakan jaminan perlindungan, pencegahan, dan pemberantasan kasus-kasus kekerasan melalui legalisasi produk hukum yang lebih berperspektif jender. Dalam hal ini, upaya strategis yang pertama kali mereka lakukan adalah mendesak Pemerintah untuk membentuk sebuah komisi nasional yang bertugas memonitor tindakan pencegahan dan pemberantasan kekerasan terhadap perempuan. Upaya ini membuahkan hasil 109 dengan keluarnya Kepres No. 181 tahun 1998 mengenai dibentuknya Komisi Nasional tentang Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Selanjutnya, Komnas bersama LSM lain menyusun berbagai rencana aksi nasional untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan, termasuk KDRT. Di antaranya adalah melalui penyusunan undang-undang terkait dengan isu-isu tersebut sekaligus melalui pemberian advokasi panjang dan berbagai kampanye untuk mensosialisasikannya ke tengah-tengah masyarakat. Hasilnya, salah satunya, adalah digolkannya RUU KDRT menjadi UU. Upaya untuk mengatur kekerasan dalam rumah tangga ke dalam suatu perundang-undangan telah dilakukan melalui Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undangundang tersebut merupakan tuntutan masyarakat yang telah sesuai dengan tujuan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 untuk menghapus segala bentuk kekerasan di Indonesia, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu juga, sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan. Dengan demikian, terlihat ada perubahan pandangan dari pemerintah mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, tidak semata-mata merupakan urusan privat, tetapi juga menjadi masalah publik, dari urusan rumah tangga menjadi urusan publik yang diatur melalui Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Harus diakui, kemunculan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disambut dengan beragam respon, baik pro maupun kontra. 110 Namun, kepedulian dan perlindungan terhadap korban kekerasan rumah tangga tidak boleh berhenti dan tetap terus digalang. 2. Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga Kekerasan (fisik, psikis dan seksual) terjadi dimana-mana dan cenderung makin meningkat. Banyak sekali kasus kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence) tidak dilaporkan kepada polisi untuk ditindak sebagaimana mestinya, dan makin sedikit lagi yang diselidiki, disidik, dan dituntut di depan pengadilan. Data yang tersedia baik di tingkat regional maupun pusat tentang kekerasan tersebut sangat langka, yang sesungguhnya diperlukan untuk menetapkan berbagai kebijakan untuk mencegah merajalelanya kekerasan. Salah satunya yaitu Tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kejahatan yang sangat menyengsarakan dalam waktu yang panjang. Sebagai akibat ”nonreporting crimes” seperti ini selain para korban harus menderita dalam kediaman (suffering in silence), para pelakunya juga jarang yang diproses dalam sistem peradilan pidana.116 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) cenderung dilakukan oleh pria pada kelompok usia yang masih muda, tidak bekerja, tidak dalam ikatan pernikahan yang sah, kemungkinan pernah menyaksikan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada masa kanak-kanak, serta adanya problem psikiatri yang bervariasi dari depresi sampai penyalahgunaan zat berbahaya. Beberapa keadaan lain yang 116 Harkristuti Harkrisnowo, 2007, Menggugat Eksistensi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, FH – UI , Jakarta, h. 142. 111 perlu mendapat perhatian terhadap kemungkinan terjadinya KDRT adalah masalah terkait obat-obatan dan alkohol, situasi yang berkaitan dengan keadaan stress dan depresi. Banyak pelaku KDRT melakukan kekerasan di bawah pengaruh alkohol. Namun pelaku yang melakukan kekerasan dalam kondisi sadar mengambil proporsi yang lebih besar. Pelaku KDRT dapat dibedakan menjadi tiga tipe : - - - cyclically emotional volatile perpetrators, pelaku KDRT jenis ini mempunyai ketergantungan terhadap keberadaan pasangannya. Pada dirinya telah berkembang suatu pola peningkatan emosi yang diikuti dengan aksi agresif terhadap pasangan. Bila pelaku memulai dengan kekerasan psikologis, kekerasan tersebut dapat berlanjut pada kekerasan fisik yang berat. overcontrolled perpetrators, pelaku jenis ini yaitu kelompok yang pada dirinya telah terbentuk pola kontrol yang lebih mengarah kepada kontrol psikologis daripada kekerasan fisik. Psychopathic perpetrators, pelaku yang pada dirinya tidak terbentuk hubungan emosi atau rasa penyesalan, dan cenderung terlibat juga dalam kekerasan antar pria maupun perilaku kriminal lainnya.117 Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tersebut antara lain untuk : a) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; b) melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; c) menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan d) memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Beranjak dari tujuan yang demikian, maka pemerintah mempenalisasi tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan pidana yang jauh lebih berat daripada ketentuan dalam KUHP. Tindak pidana yang dikategorikan sebagai 117 Core Group, Modul Konseling bagi Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga, Mitra Perempuan Workshop, Jakarta, 27 Juni 2008, h. 7. 112 kekerasan dalam rumah tangga juga ditambah dengan “tindak pidana penelantaran rumah tangga”. Undang-undang ini tidak hanya memuat ketentuan pidana, tapi juga ketentuan tentang perlindungan (dalam bentuk beberapa hak) dan layanan terhadap korban KDRT, kewajiban aparat penegak hukum, serta pihak yang terkait dalam pemberian perlindungan tersebut). Keseluruhannya dengan maksud untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 4 undangundang tersebut. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memuat alternatif pengaturan sanksi pidana bagi pelaku dan tujuannya juga meliputi korektif, preventif dan protektif, yang juga berdasarkan tingkat ringan dan beratnya tindak KDRT. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah undang-undang yang mengatur permasalahan spesifik secara khusus, sehingga memuat unsur-unsur lex special. Unsur-unsur lex special terdiri dari : - Unsur korektif terhadap pelaku, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur alternatif sanksi dari pada KUHP yang hanya mengatur pidana penjara dan denda, yakni berupa kerja sosial dan program intervensi yang diberlakukan tehadap pelaku. Hal ini dimaksudkan agar pelaku tidak kembali melakukan tindak kekerasan. - Unsur preventif terhadap masyarakat, Keberadaan Undang- Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ditujukan untuk mencegah tindak kekerasan yang terjadi pada lingkup rumah tangga, 113 karena selama ini masalah kekerasan dalam rumah tangga dianggap masalah privat sehingga kekerasan yang terjadi tidak mudah di intervensi. - Unsur Protektif terhadap korban, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memuat pasal-pasal yang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam hubunganhubungan domestik, khususnya terhadap pihak-pihak yang tersubordinasi (kelompok rentan yaitu : wanita dan anak-anak). 3.2. Formulasi Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) cenderung dilakukan oleh pria pada kelompok usia yang masih muda, tidak bekerja, tidak dalam ikatan pernikahan yang sah, kemungkinan pernah menyaksikan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada masa kanak-kanak, serta adanya problem psikiatri yang bervariasi dari depresi sampai penyalahgunaan zat berbahaya. Beberapa keadaan lain yang perlu mendapat perhatian terhadap kemungkinan terjadinya KDRT adalah masalah terkait obat-obatan dan alkohol, situasi yang berkaitan dengan keadaan stress dan depresi. Banyak pelaku KDRT melakukan kekerasan di bawah pengaruh alkohol. Namun pelaku yang melakukan kekerasan dalam kondisi sadar mengambil proporsi yang lebih besar. Pelaku KDRT dapat dibedakan menjadi tiga tipe : - cyclically emotional volatile perpetrators, pelaku KDRT jenis ini mempunyai ketergantungan terhadap keberadaan pasangannya. Pada 114 dirinya telah berkembang suatu pola peningkatan emosi yang diikuti dengan aksi agresif terhadap pasangan. Bila pelaku memulai dengan kekerasan psikologis, kekerasan tersebut dapat berlanjut pada kekerasan fisik yang berat. - overcontrolled perpetrators, pelaku jenis ini yaitu kelompok yang pada dirinya telah terbentuk pola kontrol yang lebih mengarah kepada kontrol psikologis daripada kekerasan fisik. - Psychopathic perpetrators, pelaku yang pada dirinya tidak terbentuk hubungan emosi atau rasa penyesalan, dan cenderung terlibat juga dalam kekerasan antar pria maupun perilaku kriminal lainnya.118 - penyesalan, dan cenderung terlibat juga dalam kekerasan antar pria ataupun perilaku kriminal - lainnya. 1. Perumusan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Istilah “pidana” berasal dari bahasa Sansekerta (dalam bahasa Belanda disebut “straf” dan dalam bahasa Inggris disebut “penalty”) yang artinya “hukuman”. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, “pidana” adalah “hukuman”.119 Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan pemidanaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana. Masalah tindak pidana merupakan masalah 118 119 Core Group, Modul Konseling bagi Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga, Mitra Perempuan Workshop, Jakarta, 27 Juni 2008, hal : 7. Subekti dan Tjitrosoedibio, 1980, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 83. 115 kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya. KUHP membedakan “aturan umum” untuk tindak pidana yang berupa kejahatan dan pelanggaran. Artinya, kualifikasi delik berupa kejahatan atau pelanggaran merupakan kualifikasi juridis yang akan membawa konsekuensi juridis yang berbeda. KUHP tidak mengenal kualifikasi juridis berupa delik aduan, walaupun di dalam KUHP ada aturan umum tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan untuk kejahatan-kejahatan tertentu (tidak untuk pelanggaran). KUHP tidak membuat aturan umum untuk bentuk-bentuk tindak pidana (“forms of criminal offence”) yang berupa permufakatan jahat, persiapan, dan pengulangan (recidive). Ketiga bentuk tindak pidana ini hanya diatur dalam aturan khusus (Buku II atau Buku III). Artinya, ketentuan mengenai permufakatan jahat, persiapan, dan pengulangan di dalam KUHP hanya berlaku untuk delikdelik tertentu dalam KUHP, tidak untuk delik di luar KUHP. Pada umumnya dalam setiap perbuatan antara pelaku dan korban seringkali tidak saling kenal malah terkesan asing. Memang ada beberapa perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah saling mengenal (sahabat, teman, tetangga), serta orang-orang yang mempunyai hubungan darah. Sebetulnya bentuk tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga juga sama 116 dengan bentuk-bentuk tindak pidana pada umumnya misalnya penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP, pembunuhan (Pasal 338 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP), dan penghinaan (Pasal 310 KUHP), Perzinahan (Pasal 284 KUHP) dan perbuatan-perbuatan lain yang dapat dikategorikan perbuatan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, kekerasan dalam rumah tangga mempunyai sifat uang khusus dan karakteristik yang terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, locus delicti-nya serta cara-cara penyelesaiannya. Perumusan norma atau kaidah di dalam undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dituangkan di dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9. Di dalam Pasal 5 UU No. 23 tahun 2004 dinyatakan, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang lingkup rumah tangganya dengan cara : a. kekerasan fisik; b. Kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga. Di dalam Pasal 6 dinyatakan bahwa, kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perubahan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Korelasi lain bahwa KDRT adalah merupakan bentuk kekerasan berbasis gender dan juga sebagai bentuk diskriminasi, adalah sebagaimana dinyatakan dalam Alinea keempat Penjelasan Umum UU-PKDRT, yang menegaskan : “...Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi”. Pernyataan atas pandangan negara tersebut adalah sebagaimana diamanatkan 117 dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya, dan amanat Pasal 28G ayat (1) menentukan bahwa : “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Selanjutnya Pasal 7 memuat pernyataan bahwa, kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan /atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Sementara itu, dalam Pasal 8 dinyatakan, kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi : (a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang menetapkan dalam lingkup rumah tangga tersebut, (b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertantu. Kemudian di dalam Pasal 9 dinyatakan, (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; (2) 118 Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Di dalam Undang-undang ini juga dinyatakan bahwa, tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan (Pasal 51). Demikian juga, tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan (Pasal 52). Demikian juga halnya, tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan (Pasal 53). 2. Delik Aduan Kekerasan dalam Rumah Tangga Setiap kejahatan yang terjadi akan menimbulkan korban. Yang di maksud dengan korban kejahatan adalah : “mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”.120 Dalam pasal 108 ayat (1) KUHP menentukan bahwa: “Setiap orang yang mengalami atau menjadi korban suatu tindak pidana itu berhak mengajukan pengaduan”, kiranya perlu diingat bahwa menurut ketentuanketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak semua orang berhak untuk mengajukan Pengaduan tindak pidana yang dilihatnya, oleh karena ada tindak pidana yang terjadi itu baru dapat dilakukan penyidikan jika ada pengaduan dari si korban (dalam hal delik aduan). Dalam 120 Gosita, Arief, Op.cit, h. 41. 119 delik aduan, keadaan di atas menjadi penting bagi para penyidik, yakni agar pengaduan tersebut dapat dipakai sebagai dasar yang sah untuk melakukan penyidikan, dan guna mencegah agar penyidik jangan sampai dipersalahkan karena telah melakukan penyidikan yang tidak berdasarkan undang-undang. Delik aduan (klacht delict) pada hakekatnya juga mengandung elemenelemen yang lazim dimiliki oleh setiap delik. Delik aduan punya ciri khusus dan kekhususan itu terletak pada “penuntutannya”. Lazimnya, setiap delik timbul, menghendaki adanya penuntutan dari penuntut umum, tanpa ada permintaan yang tegas dari orang yang menjadi korban atau mereka yang dirugikan. Dalam delik aduan, pengaduan dari si korban atau pihak yang dirugikan adalah syarat utama untuk dilakukannya hak menuntut oleh Penuntut Umum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), secara tegas tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan delik aduan. Pengertian dan defenisi yang jelas dapat ditemui melalui argumentasi dari pakarpakar dibidang ilmu pengetahuan hukum pidana, seperti yang diuraikan berikut ini : a) Menurut Samidjo, delik aduan (Klacht Delict) adalah suatu delik yang diadili apabila yang berkepentingan atau yang dirugikan mengadukannya. Bila tidak ada pengaduan, maka Jaksa tidak akan melakukan penuntutan. b) Menurut R. Soesilo dari banyak peristiwa pidana itu hampir semuanya kejahatan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan 120 (permintaan) dari orang yang kena peristiwa pidana. Peristiwa pidana semacam ini disebut delik aduan.121 c) Menurut Lamintang, tindak pidana tidak hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Tindak pidana seperti ini disebut Klacht Delicten.122 Menurut pendapat para sarjana diatas, kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah bahwa untuk dikatakan adanya suatu delik aduan, maka disamping delik tersebut memiliki anasir yang lazim dimiliki oleh tiap delik, delik ini haruslah juga mensyaratkan adanya pengaduan dari si korban atau pihak yang dirugikan untuk dapat dituntutnya si pelaku. Dari beberapa pendapat diatas walaupun dirasa sudah menggambarkan secara jelas bagaimana karakter serta sifat hakekat dari delik aduan itu, namun demikian masih dirasakan sedikit kekurangan. Kekurangan itu adalah dalam hal “penuntutan”. Tegasnya para pakar tidak memperhitungkan adanya kemungkinan penggunaan asas opportunitas dalam definisi yang mereka kemukakan. Jadi walaupun hak pengaduan untuk penuntutan perkara ada pada si korban. Pada akhirnya, untuk dituntut atau tidak adalah semata-mata digantungkan kepada Penuntut Umum. Untuk itu, akan lebih sempurna apabila definisi tentang delik aduan itu diberi tambahan dalam penggunaan asas opportunitas (asas mengeyampingkan perkara demi kepentingan umum atau perkara tidak dilimpahkan ke pengadilan demi kepentingan umum) karena dalam hal 121 122 Soesilo, 1993, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, h. 87. Lamintang, op. cit, h. 217. 121 penuntutan perkara penggunaan asas ini selalu dipertimbangkan pemberlakuannya. Delik aduan (Klacht Delicten) ini adalah merupakan suatu delik, umumnya kejahatan, dimana untuk penuntutan perkara diharuskan adanya pengaduan dari si korban atau pihak yang dirugikan sepanjang Penuntut Umum berpendapat kepentingan umum tidak terganggu dengan dilakukannya penuntutan atas perkara tersebut. Alasan persyaratan adanya pengaduan tersebut menurut Simons yang dikutip oleh Satochid adalah : “adalah karena pertimbangan, bahwa dalam beberapa macam kejahatan, akan lebih mudah merugikan kepentingankepentingan khusus (bizjondere belang) karena penuntutan itu, daripada kepentingan umum dengan tidak menuntutnya”.123 Dengan latar belakang alasan yang demikian, maka tujuan pembentuk undang-undang adalah memberikan keleluasaan kepada pihak korban atau pihak yang dirugikan untuk berpikir dan bertindak, apakah dengan mengadukan perkaranya akan lebih melindungi kepentingannya. Apakah itu menguntungkan ataukah dengan mengadukan perkaranya justru akan merugikan kepentingan pihaknya (contoh : tercemarnya nama baik keluarga, terbukanya rahasia pribadi atau kerugian lainnya). Pada akhirnya inisiatif untuk mengadukan dan menuntut perkara sepenuhnya (dengan tidak mengindahkan asas opportunitas) berada pada si korban atau pihak yang dirugikan. Bila keberadaan asas opportunitas tidak diindahkan, maka keleluasaan untuk mengadu atau tidak mengadu yang ada pada 123 Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian II, Balai Lektur Mahasiswa, Bandung, h. 165. 122 si korban atau pihak yang dirugikan, dan tepatlah praduga sebagaimana yang dikemukakan diatas. Tetapi nyatanya, hal seperti ini ada kalanya tidak sepenuhnya berlaku. Dalam hal dan keadaan tertentu, penghargaan dan kesempatan (keleluasaan) yang diberikan itu tidak mempunyai arti apapun bilamana persoalannya diadakan pengusutan untuk kemudian dilakukan penuntutan oleh Penuntut Umum dengan hak opportunitasnya. Maka pada keadaan ini prinsip umum yang biasa berlaku dalam suatu delik yakni hak untuk melakukan penuntutan diletakkan pada Penuntut Umum kembali diberlakukan. Satochid Kartanegara, memberikan rumusan delik aduan sebagai berikut, delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan (klacht).124 Gerson W. Bawengan membedakan delik aduan atas dua bagian yaitu delik aduan mutlak dan delik aduan relatif. Sementara Satochid membedakannya atas delik pengaduan absolut (absolute klachtdelicten) dan delik aduan relatif (relative klachtdelicten). Dari kedua ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa delik aduan dibedakan atas dua jenis, yaitu : a) Delik aduan absolut atau mutlak (absolute klachtdelicten) Delik aduan absolut atau mutlak adalah beberapa kejahatankejahatan tertentu yang untuk penuntutannya pada umumnya dibutuhkan pengaduan. Sifat pengaduan dalam delik aduan absolut (absolute klachtdelicten) ialah, bahwa pengaduan tidak boleh dibatasi pada beberapa orang tertentu, melainkan dianggap ditujukan kepada siapa saja yang 124 Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian I, Balai Lektur Mahasiswa, Bandung, h. 154. 123 melakukan kejahatan yang bersangkutan. Dalam hal ini dikatakan, bahwa pengaduan ini tidak dapat dipecah-pecah (onsplitsbaar). Delik aduan absolut ini merupakan pengaduan untuk menuntut peristiwanya, sehingga pengaduan berbunyi : “saya minta agar peristiwa ini dituntut”. Jika pengaduan itu sudah diterima, maka Jaksa berhak untuk menuntut segala orang yang turut campur dalam kejahatan itu. Pengaduan tentang kejahatan-kejahatan aduan absolut mengenai perbuatan, bukan pembuat atau orang lain yang turut campur didalamnya. Karena itu pengadu tidak berhak membatasi hak menuntut, yakni supaya yang satu dituntut dan yang lain tidak. Larangan ini dinyatakan dengan perkataan : “Pengaduan tentang kejahatan-kejahatan aduan absolut tak dapat dibelah”. Contoh : A, istrinya B, mengaku pada suaminya, bahwa ia pernah terlena terhadap godaan C, sehingga ia berzina dengan C. Karena istrinya sangat menyesal tentang peristiwa itu, maka B mengampuni akan tetapi ia mengirim suatu permohonan kepada jaksa supaya C dituntut lantaran perkara itu. Secara formil permohonan ini harus ditolak karena menurut Pasal 284 ayat (2) “perzinahan” adalah kejahatan aduan absolut, jadi A hanya boleh mengadu tentang peristiwa itu, tidak kepada seorang khusus yang turut campur didalamnya. Kepada B harus diberitahukan, bahwa permohonannya baru dianggap sebagai pengaduan yang sah, jika ia menyatakan kehendaknya akan menyerahkan kepada jaksa keputusan apakah istrinya dituntut. Kejahatan-kejahatan yang termasuk didalam delik aduan absolut yang diatur dalam KUHP, yaitu : 124 1) Kejahatan Kesusilaan (zedenmisdrijven), yang diatur dalam Pasal 284 tentang “zina” (overspel), Pasal 287 tentang “perkosaan” (verkrachting), Pasal 293 tentang “perbuatan cabul” (ontucht), didalam salah satu ayat dari pasal itu ditentukan bahwa penuntutan harus dilakukan pengaduan. 2) Kejahatan Penghinaan, yang diatur dalam Pasal 310 tentang “menista” (menghina), Pasal 311 tentang “memfitnah” (laster), Pasal 315 tentang “penghinaan sederhana” ( oenvoudige belediging), Pasal 316 (penghinaan itu terhadap seorang pejabat pemerintah atau pegawai negeri yang sedang melakukan tugas secara sah, untuk menuntutnya berdasarkan Pasal 319, tidak diperlukan pengaduan), Pasal 319 (disini ditentukan syaratnya bahwa kejahatan penghinaan dapat dituntut setelah oleh pihak penderita dilakukan pengaduan kecuali dalam hal Pasal 316, hal ini merupakan penyimpangan dari ketentuan delik aduan itu sendiri). 3) Kejahatan membuka rahasia (schending van geheimen), yang diatur dalam Pasal 322 dan Pasal 323, yaitu bahwa guna melakukan penuntutan terhadap kejahatan ini harus dilakukan pengaduan, ditentukan dalam ayat terakhir dari kedua pasal itu. 4) Kejahatan mengancam (afdreiging), yang diatur dalam Pasal 369 bahwa dalam ayat (2) ditentukan bahwa diperlukan pengaduan untuk mengadakan penuntutan. 125 Selain kejahatan-kejahatan aduan absolut yang diatur didalam KUHP, diluar KUHP terdapat juga pengaturan mengenai kejahatan aduan tersebut, seperti: kekerasan dalam rumah tangga yang diatur didalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). Pasal 51-53 menentukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang termasuk kedalam delik aduan. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut, yaitu : 1) Tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Hal tersebut diatur didalam Pasal 51 jo Pasal 44 ayat (4) UUPKDRT. Menurut Pasal 6 UUPKDRT, yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. 2) Tindak pidana kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Hal tersebut diatur didalam Pasal 52 jo Pasal 45 ayat (2) UUPKDRT. Menurut Pasal 7 UUPKDRT, yang dimaksud dengan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, 126 dan/atau penderitaan psikis, berat pada seseorang. Tindak pidana kekerasan seksual yang meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya. Dengan ditentukannya beberapa jenis kekerasan dalam rumah tangga tersebut sebagai delik aduan, pembentuk undang-undang (UndangUndang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) telah mengakui adanya unsur privat/pribadi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. b) Delik aduan relatif (relative klachtdelicten) Delik aduan relatif adalah beberapa jenis kejahatan tertentu yang guna penuntutannya pada umumnya tidak dibutuhkan pengaduan, tetapi dalam hal ini hanya ditentukan bahwa pengaduan itu merupakan syarat, apabila diantara si pembuat dan si pengadu terdapat hubungan tertentu. Hubungan tertentu antara si pembuat dan si pengadu ialah hubungan keluarga-keluarga sedarah dalam garis lurus (bapak, nenek, anak, cucu) atau dalam derajat kedua dari garis menyimpang (saudara) dan keluargakeluarga perkawinan dalam garis lurus (mertua, menantu) atau dalam derajat kedua dari garis menyimpang (ipar). Contoh-contoh delik aduan relatif yang diatur secara tersendiri dalam KUHP, yaitu : 1) Pasal 362 tentang kejahatan pencurian (diefstal), 2) Pasal 367 tentang kejahatan pencurian yang biasa disebut “pencurian di dalam lingkungan keluarga”, 3) Pasal 369 jo Pasal 370 jo Pasal 367 tentang pemerasan dengan menista (afdreigging atau chantage), misalnya A 127 mengetahui rahasia B, kemudian datang pada B dan minta supaya B memberi uang kepada A dengan ancaman, jika tidak mau memberikan uang itu, rahasianya akan dibuka. OLeh karena B takut akan dimalukan, maka ia terpaksa memberi uang itu, 4) Pasal 372 jo Pasal 376 jo Pasal 367 tentang penggelapan yang dilakukan dalam kalangan kekeluargaan, 5) Pasal 378 jo Pasal 394 jo Pasal 367 tentang penipuan yang dilakukan dalam kalangan kekeluargaan. Hubungan kekeluargaan harus dinyatakan pada waktu mengajukan pengaduan. Penuntutan hanya terbatas pada orang yang disebutkan dalam pengaduannya. Apabila, misalnya, yang disebutkan ini hanya si pelaku kejahatan, maka terhadap si pembantu kejahatan, yang mungkin juga berkeluarga dekat, tidak dapat dilakukan penuntutan. Dengan demikian pengaduan ini adalah dapat dipecah-pecah (splitsbaar). Dari pasal-pasal yang tercantum mengenai delik aduan itu, penggunaan istilah “hanya dapat dilakukan penuntutan kalau ada pengaduan”. Maka kalimat itu menimbulkan pemikiran atau pendapat bahwa dengan demikian pengusutan dapat dilakukan oleh pihak petugas hukum demi untuk kepentingan preventif. Walaupun pendapat demikian itu adalah benar, namun untuk kepentingan tertib hukum, adalah lebih beritikad baik bilamana pengusutan itu diajukan secara lisan dari pihak yang dirugikan bahwa ia akan mengajukan 128 pengaduan. Menurut Modderman, ada alasan khusus dijadikannya kejahatankejahatan aduan relatif bilamana dilakukan dalam kalangan keluarga,125 yaitu : 1) Alasan susila, yaitu untuk mencegah pemerintah menghadapkan orang-orang satu terhadap yang lain yang masih ada hubungan yang sangat erat dan dalam sidang pengadilan, 2) Alasan materiil (stoffelijk), yaitu pada kenyataannya di dalam suatu keluarga antara pasangan suami istri dan istri ada semacam condominium. Baik delik aduan absolut maupun delik aduan relatif yang sering disebut aduan saja, dimaksudkan untuk mengutamakan kepentingan pihak yang dirugikan dari pada kepentingan penuntutan. Dengan kata lain pembuat undangundang memberikan penghargaan kepada pihak yang dirugikan dan kesempatan untuk mengadakan pilihan, apakah ia bermaksud untuk mengajukan pengaduan atau mendiamkan persoalan, misalnya demi untuk nama baik keluarga ataupun mungkin untuk menyimpan sebagai rahasia yang tidak perlu diketahui orang banyak. Menurut Utrecht alasan satu-satunya pembentuk undang-undang untuk menetapkan suatu delik aduan adalah pertimbangan bahwa dalam beberapa hal tertentu pentingnya bagi yang dirugikan supaya perkaranya tidak dituntut adalah lebih besar dari pada pentingnya bagi negara supaya perkara itu dituntut .126 Konsekuensi yuridis dari penentuan tersebut adalah aparat penegak hukum tidak dapat melakukan tindakan hukum apapun terhadap pelaku, meskipun 125 126 Adami Chazawi, 2005, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 205. Utrecht, 2000, Hukum Pidana II, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, h. 257. 129 mereka mengetahui bahwa tindak pidana telah terjadi, jika korban dari tindak pidana tersebut melakukan pengaduan. Dalam UUPKDRT ditentukannya beberapa pasal yang termasuk ke dalam delik aduan, maka ketentuan dalam Bab VII KUHP tentang, memasukkan dan mencabut pengaduan dalam perkara kejahatan, yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, berlaku untuk UUPKDRT. Dalam UUPKDRT tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai tenggang waktu seseorang diperbolehkan untuk mengadu dan tenggang waktu seseorang diperbolehkan untuk mencabut pengaduannya. Sehingga mengenai tenggang waktu tersebut berlakulah Pasal 74 KUHP tentang tenggang waktu diperbolehkannya untuk mengadu, yaitu : 1) Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia. 2) Jika yang terkena kejahatan berhak mengadu pada saat tenggang waktu tersebut dalam ayat 1 belum habis, maka setelah saat itu, pengaduan masih boleh diajukan hanya selama sisa yang masih kurang pada tenggang waktu tersebut. Sedangkan Pasal 75 KUHP mengatur tentang tenggang waktu mencabut pengaduan, yaitu : Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan. Dengan ditetapkannya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga baik fisik, psikis, kekerasan seksual maupun penelantaran dalam rumah tangga 130 sebagai delik aduan memang ditujukan untuk memperhatikan kepentingan korban, namun dalam beberapa hal misalnya terhadap tindak pidana kekerasan fisik dan kekerasan seksual ada baiknya untuk diarahkan menjadi delik biasa atau delik pidana umum. Pertimbangan dari perubahan delik aduan menjadi delik biasa tersebut dilihat dari akibat serta dampak dari tindak pidana yang dapat dibuktikan tidak hanya berdasarkan pengaduan korban, dan merupakan kewajiban dari negara untuk melindungi warga negaranya yang telah nyata-nyata dilanggar HAM-nya. BAB IV KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERUMUSAN SISTEM SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KDRT 4.1. Cara Perumusan Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana 1. Pengertian Sanksi Pidana Menurut Andi Hamzah,127 ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah straf. 127 Andi Hamzah, Op.cit, h. 27. 131 Istilah hukuman128 adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana. Hukuman atau pidana yang dijatuhkan dan perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana, harus lebih dahulu tercantum dalam undang-undang pidana. Suatu asas yang disebut dengan nullum crimen sine lege, yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.129 Menurut Satochid Kartanegara,130 bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang justru akan dilindungi oleh undang-undang hukum pidana. Kepentingan hukum yang akan dilindungi itu adalah sebagai berikut : 128 129 130 Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta, h. 20. Van Bemmelen, 1987, Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum, Binacipta, Bandung, h. 17. Satochid Kartanegara, 1954-1955, Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Bandung, h. 275-276. 132 a) Jiwa manusia (leven); b) Keutuhan tubuh manusia (lyf); c) Kehormatan seseorang (eer); d) Kesusilaan (zede); e) Kemerdekaan pribadi (persoonlyke vryheid); f) Harta benda/kekayaan (vermogen). Berikut ini dikutip pengertian pidana yang dikemukakan oleh beberapa ahli : Menurut van Hamel : “een bijzonder leed, tegen den overtreder van een door den staat gehandhaafd rechtsvoorschrift, op den enkelen grond van die overtreding, van wege den staat als handhaver der openbare rechtsorde, door met de rechtsbedeeling belaste gezag uit te spreken.”131 Artinya : Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. Menurut Simons : “Het leed, door de strafwet als gevolg aan de overtreding van de norm verbonden, dat aan den schuldige bij rechterlijk vonnis wordt opgelegd”.132 Artinya: suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. 131 132 Lamintang, 1984, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, h. 34. Ibid, h. 35. 133 Menurut Sudarto : Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.133 Menurut Roeslan Saleh : Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.134 Menurut Ted Honderich : Punishment is an authority’s infliction of penalty (something involving deprivation or distress) on an offender for an offence.135 Artinya : pidana adalah suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman (sesuatu yang meliputi pencabutan dan penderitaan) yang dikenakan kepada seorang pelaku karena sebuah pelanggaran. 2. Perumusan Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Semua hukum pidana materiil/substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan (the sentencing system). L.H.C Hulsman mengemukakan pengertian sistem pemidanaan sebagai : aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan” (the statory rules relating to penal sanctions and punishment). Dari pengertian di atas Barda Nawawi Arief memberikan pengertian oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup pengertian :136 • 133 134 135 136 Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan; Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.cit, h. 1. Ibid, h. 1. Muhammad Taufik Makarao, 2005, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan, Kreasi Wacana, Yogyakarta, h. 18. Barda Nawawi I, Op.cit, h. 136. 134 • Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana. • Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana; • Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalisasikan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Berdasarkan hasil penelitian Muladi, pemidanaan mempunyai tujuan integratif yaitu perlindungan masyarakat, pemeliharaan solidaritas masyarakat, pencegahan umum dan khusus, dan pengimbalan/ pengimbangan. Teori integratif memungkinkan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus, yang secara terpadu diarahkan untuk mengatasi dampak individual dan sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana atas dasar kemanusiaan dalam sistem Pancasila. Kombinasi tersebut mencakup seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi oleh setiap penjatuhan sanksi pidana. Ini selaras dengan kondisi filosofis, sosiologis, dan ideologis masyarakat Indonesia.137 Ada 4 tujuan pemidanaan dalam teori pemidanaan integratif : a. Memberikan perlindungan masyarakat Pengertian perlindungan masyarakat mengarah pada semua keadaan yang mendukung agar masyarakat terlindung dari bahaya pengulangan tindak pidana. Tujuan ini merupakan tujuan setiap pemidanaan.138 b. 137 138 Pemeliharaan solidaritas masyarakat Muladi II, Op.cit, h. 11. Muladi II, Op.cit, h. 84. 135 Pemeliharaan solidaritas mengarah pada upaya penegakkan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat dan pencegahan balas dendam perseorang atau balas dendam tidak resmi (private revenge or unofficial retaliation) terhadap penjahat. Selain itu, solidaritas masyarakat seringkali dikaitkan dengan kompensasi terhadap korban kejahatan berupa ganti kerugian. c. Sarana pencegahan umum dan pencegahan khusus Pencegahan umum ditujukan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan pencegahan khusus ditujukan agar pelaku tindak pidana yang sudah dijatuhi pidana tidak melakukan tindak pidana lagi di kemudian hari. Muladi menyebutkan, bahwa dalam pencegahan khusus mencakup 3 faktor utama, yaitu tipologi kejahatan, karakteristik pelaku kejahatan, kepastian dan kecepatan hukum.139 d. Pengimbalan/ Pengimbangan Pengertian pengimbalan/ pengimbangan adalah diperlukannya keseimbangan antara perbuatan pidana dengan pidana yang dijatuhkan. Hal ini perlu diperhatikan dalam setiap tahap pembinaan. Dalam sejarah perkembangan hukum pidana dapat diungkapkan adanya 3 macam teori yang mengemukakan tujuan pemidanaan, teori tersebut mengkaji tentang alasan pembenar penjatuhan pidana, yaitu : 1. Teori Absolut (vergelding theorien) Menurut teori ini, pidana sama sekali tidak mengandung pertimbangan tujuan dan manfaat bagi terpidana. Pidana hanya dimaksudkan untuk memberikan nestapa guna memberi imbangan agar tercipta ketertiban 139 Muladi II, Op.cit, h. 82 136 hukum.140 Ketertiban hukum merupakan kehendak semua orang, yaitu tesis (Position), berhadapan dengan kehendak khusus dari pelaku, yang dimanifestasikan dengan perbuatannya, yaitu antitesis (negotion). Pidana (sintesis) dianggap sebagai sarana untuk menetralkan tesis dan antitesis tersebut. Dasar pijakan teori absolut dalam penjatuhan pidana adalah pada aspek pembalasan yang setimpal kepada penjahat, karena itu teori ini disebut juga teori pembalasan. Siapa saja berbuat jahat harus dipidana tanpa melihat akibat-akibat apa saja yang timbul setelah penjatuhan pidana, baik terhadap terpidana maupun masyarakat. Faktor yang dipertimbangkan hanya masa lalu terpidana, tidak melihat masa depan terpidana. Tujuan pemidanaan adalah menjadikan si penjahat menderita, dengan jalan menjatuhkan pidana sebagai pembalasan.141 Pembalasan tersebut dipandang sebagai suatu reaksi keras yang bersifat emosional, karena itu mempunyai sifat yang irasional.142 2. Teori Relatif (doel theorien) Dalam perkembangan pemikiran pemidanaan selanjutnya, lahir teori relatif atau lazim disebut teori tujuan atau teori prevensi. Teori tujuan ini bukan merupakan penyempurnaan atau perbaikan atas ketidakberhasilan teori pembalasan.143 Dalam teori relatif, tujuan pidana diarahkan pada usaha agar kejahatan yang telah dilakukan oleh penjahat tidak terulang lagi. Penjatuhan 140 Soemitro, 1996, Actuele Crimminologie, Universitas Sebelas Maret Press, Surakarta, h. 218. 141 142 143 Made Sadhi Astuti, 1997, Pemidanaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana, IKIP Malang, Malang, h. 32. Sahetapy, 1998, Kriminologi, Rajawali, Jakarta, h. 11. Made Sadhi Astuti, Op.cit, h. 33. 137 pidana bukan hanya memperhatikan masa lalu penjahat, melainkan juga masa depannya.144 Teori prevensi melihat pada sifat berbahayanya pribadi si pelaku kejahatan, dan terhadap mereka yang mempunyai kecenderungan untuk melakukan perbuatan jahat, tidak memandang penjatuhan pidana sebagai suatu konsekuensi atas kesalahan yang sudah dilakukan oleh seseorang pada masa lalu, melainkan untuk mencegah terulangnya kejahatan. Teori prevensi menganggap bahwa kesalahan seseorang berada di luar perhatiannya. Pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan di masa mendatang. Perbuatan manusia bukan menjadi dasar hukum atau alasan untuk menjatuhkan pidana, melainkan hanya dianggap sebagai keadaan yang menimbulkan pidana. Tindak pidana merupakan petunjuk tentang adanya keadaan bahaya, untuk itu negara harus melakukan reaksi berupa penjatuhan pidana. Dalam kaitannya dengan elemen teori prevensi, Gennaro F. Vito dan Ronald M. Holmes menulis sebagai berikut : Elements of deterrence theory a. The primary assumtion behind deterrence theory is that individual have free will and are rational; b. In order for punishment to have the maximum detterent effect, they should guarantee that the anticipated benefits from a criminal act will not be enjoyed; c. Certainly of punishment (especially of apprehension) is more important then severity of punishment. The level of punishment should reflect the severity of the crime; d. Punishment should be uniform : all persons, regardless of their position, status, or power, convicted of the same crime punishment; e. All penalties should be known in order to prevent the rational individual from commiting crime.145 144 Made Sadhi Astuti, Op.cit, h. 32. 138 Elemen-elemen teori prevensi adalah asumsi utama tentang manusia sebagai makhluk yang bebas berkehendak dan rasional; pidana mempunyai efek pencegahan yang maksimum, dan menjamin kemanfaatan yang dapat mengantisipasi perbuatan pidana; penentuan pidana yang tepat lebih penting daripada pidana yang kejam. Tingkatan jenis pidana sebaiknya mencerminkan tingkat kejahatan; pidana harus seragam bagi semua orang, jika menyangkut kejahatan yang sama maka posisi, status, atau kekuasaan penjahat harus diabaikan; dan semua pidana harus diketahui oleh masyarakat dalam rangka mencegah individu agar tidak melakukan kejahatan. Selanjutnya Gennaro F.Vito menjelaskan, “Deterrence general relates to the belief that if a person is punished, others will be deterred from committing the same or similar act because of a fear of the same or similar punishment. Deterrence, specific relates to the belief that if a person is punished, that person will not commit the same criminal act because of the fear of being punished once again.146 Vito dan Holmes berpendapat bahwa pencegahan umum (prevensi umum) berhubungan dengan kepercayaan bahwa jika seseorang dipidana, maka orang lain akan merasa dihalangi untuk melakukan perbuatan serupa, karena takut mendapat pidana sebagaimana telah dijatuhkan. Pencegahan khusus (prevensi khusus) berhubungan dengan kepercayaan bahwa jika seseorang dipidana, maka orang tersebut tidak akan melakukan kejahatan yang sama dikemudian hari karena takut dipidana yang ke dua kali. Pendapat ini selaras dengan pandangan Zimring sebagai berikut : There are two ways by which deterrence is intended to operate. First, apprehended and punished offenders will refain from repeating 145 146 Widodo, 2009, Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, h. 73. Widodo, Op.cit, h. 74. 139 crimes if they are certainly caught and severely punished. This is known as “specific deterrence” or “special deterrence.” Second is “general deterrence,” in which the state’s punishment of offenders serves as an example to those in the general public who have not yet commited a crime, instilling in them enough fear of state punishment to deter them from crime.147 Zimring menulis bahwa tujuan teori prevensi khusus adalah agar pelaku tidak melakukan perbuatannya kembali. Pidana digunakan sebagai sarana pencegahan agar tindak pidana tidak dilakukan oleh orang yang sama dikemudian hari. Menurut teori prevensi umum, penerapan pidana ditujukan untuk mempengaruhi perilaku seluruh masyarakat atau kelompok orang yang berisiko tinggi untuk melakukan kejahatan. Melalui ancaman pidana dalam undang-undang dan pelaksanaan pemidanaan, negara berusaha memantapkan norma dan manghilangkan kekaburan norma, untuk mengubah pelaku kejahatan yang potensial di antara para warga untuk menaati hukum. Menurut Andi Hamzah dan Siti Rahayu, tujuan pemidanaan dalam teori prevensi adalah agar kejahatan yang pernah terjadi tidak diulangi lagi. Menurut teori prevensi khusus, tujuan pemidanaan adalah memperbaiki narapidana dan agar tidak melakukan tindak pidana lagi di kemudian hari. Sedangkan menurut teori prevensi umum, tujuan pemidanaan adalah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa atau tindak pidana lainnya di kemudian hari.148 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa teori relatif berpendirian bahwa pidana dijatuhkan untuk kepentingan masa depan narapidana dan masyarakat dalam rangka menjamin ketertiban umum. Pidana 147 148 Widodo, Op.cit, h. 75. Andi Hamzah dan Siti Rahayu, Op.cit, h. 26. 140 merupakan sarana memperbaiki penjahat agar tidak melakukan kejahatan kembali (prevensi khusus), sekaligus memberi peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan (prevensi umum). 3. Teori Gabungan (vernengings theorin) Teori absolut dan teori relatif melakukan pendekatan mengenai tujuan pemidanaan secara sepihak. Teori absolut bertujuan memberikan pembalasan kepada pelaku perbuatan jahat demi keadilan, sedangkan teori prevensi berpendapat bahwa tujuan pemidanaan adalah mencegah seseorang agar tidak melakukan tindak pidana kembali, atau untuk menakut-nakuti masyarakat atau orang-orang yang berpotensi melakukan tindak pidana agar tidak melakukan tindak pidana. Berdasarkan konsepsi tersebut lahir teori gabungan yang mengakumulasikan teori absolut dengan teori relatif. Menurut teori gabungan, dalam konsepsi pemidanaan perlu adanya pemilahan antara tahap-tahap pemidanaan yang berbeda-beda, misalnya pada ancaman pidana di dalam undang-undang, proses penuntutan, proses peradilan, serta pelaksanaan pidana. Dalam setiap tahap perlu ada asas-asas tertentu yang diprioritaskan. Jaksa di dalam mengemukakan tuntutan pidana (rekuisitor), misalnya dalam tindak pidana berkategori berat dapat mengutamakan unsur pembalasan dan prevensi umum. Pada tahap pelaksanaan pidana perlu pula memperhatikan prevensi khusus, yaitu aspek resosialisasi terpidana. Untuk tindak pidana berkategori ringan, tujuan pidana lebih difokuskan pada pribadi si pelaku, dan pemberian kesempatan kepada si pelaku untuk di-resosialisasi. Pada pelaksanaan pidana denda, prevensi 141 khusus kurang berarti, tetapi justru sanksi alternatif mempunyai peran yang sangat besar. Teori gabungan terdiri atas 3 golongan, yaitu sebagai berikut : a. Teori Gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan, tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas dan cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib. b. Teori Gabungan yang menitikberatkan pada upaya mempertahankan tata tertib masyarakat. Menurut teori ini tujuan pemidanaan adalah mempertahankan tata tertib masyarakat, namun penderitaan yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. c. Teori Gabungan yang menganggap bahwa pidana memenuhi keharusan pembalasan dan keharusan melindungi masyarakat, memberikan titik berat yang sama antara pembalasan dengan perlindungan masyarakat. Tujuan pidana bertalian erat dengan jenis kejahatan yang dilakukan dan nilai-nilai budaya bangsa yang bersangkutan.149 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa teori gabungan mengutamakan pembedaan perlakuan antara penjahat satu dengan lainnya, termasuk pembedaan sifat delik yang dilakukan. Hal ini digunakan sebagai pertimbangan dalam menerapkan unsur pembalasan dan unsur prevensi dalam rangka mencapai tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Secara berurutan generasi lahirnya jenis pidana adalah sebagai berikut: 1. Generasi pertama adalah pidana penjara yang dianggap sebagai pengganti pidana badan, misalnya pidana mati, pidana mendayung kapal, kerja paksa, dan penyiksaan badan sebagaimana tertuang dalam KUHP negara-negara di Eropa Barat. 2. Generasi ke dua, yaitu bertambah mantapnya sistem pidana penjara di Eropa Barat sehingga melahirkan beberapa bentuk pidana, misalnya pidana penjara, pidana kurungan dan lahir konsepsi penentuan strafmaat ancaman dalam KUHP, yaitu minimum khusus, minimum umum, maksimum khusus, maksimum umum. 149 Widodo, Op.cit, h. 77. 142 3. Generasi ke tiga muncul sebagai akibat dari kelemahan pidana penjara terutama pidana penjara jangka pendek, sehingga muncul konsepsi pidana denda. 4. Generasi ke empat lahir sebagai reaksi terhadap keraguan atas pelaksanaan pidana denda yang diberlakukan secara meluas.150 Sanksi pidana pada umumnya dirumuskan dalam perumusan delik, walaupun ada juga yang dirumuskan terpisah dalam pasal (ketentuan khusus) lainnya. Jenis pidana yang pada umumnya dicantumkan dalam perumusan delik menurut pola KUHP ialah pidana pokok dengan menggunakan 9 (sembilan) bentuk perumusan, yaitu : 151 a. diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara tertentu; b. diancam dengan penjara seumur hidup atau penjara tertentu; c. diancam dengan pidana penjara (tertentu); d. diancam dengan pidana penjara atau kurungan; e. diancam dengan pidana penjara atau kurungan atau denda; f. diancam dengan pidana penjara atau denda; g. diancam dengan pidana kurungan; h. diancam dengan pidana kurungan atau denda; i. diancam dengan denda. Dari 9 (sembilan) bentuk perumusan di atas, dapat diidentifikasikan hal-hal sebagai berikut :152 1. KUHP hanya menganut 2 (dua) sistem perumusan, yaitu: a. perumusan tunggal yaitu hanya diancam 1 (satu) pidana pokok; b. perumusan alternatif. 2. Pidana pokok yang diancam/dirumuskan secara tunggal, hanya pidana penjara, kurungan atau denda. Tidak ada pidana mati atau penjara seumur hidup yang diancam secara tunggal. 150 151 152 Andi Hamzah, 1993, Perbandingan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, h. 18-21. Barda Nawawi I, Op.cit, h. 165-166. Barda Nawawi I, Op.cit, h. 166. 143 3. Perumusan alternatif dimulai dari pidana pokok terberat sampai yang paling ringan. Aturan pemidanaan dalam KUHP berorientasi pada “strafsoort” yang ada/ disebut dalam KUHP, baik berupa pidana pokok maupun pidana tambahan. Jenis pidana yang dirumuskan/diancamkan dalam perumusan delik hanya pidana pokok dan/atau pidana tambahannya. Pidana kurungan pengganti tidak dirumuskan dalam perumusan delik (aturan khusus), tetapi dimasukkan dalam aturan umum mengenai pelaksanaan pidana (“strafmodus”). Dilihat dari sudut “strafmaat” (ukuran jumlah/lamanya pidana), aturan pemidanaan dalam KUHP berorientasi pada sistem minimal umum dan maksimal khusus, tidak berorientasi pada sistem minimal khusus. Artinya, di dalam KUHP tidak ada aturan pemidanaan untuk ancaman pidana minimal khusus. Dengan adanya aturan pemidanaan diharapkan putusan hakim mempunyai dimensi keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak yaitu terhadap para pelaku itu sendiri, masyarakat, korban akibat tindak pidana yang telah dilakukan para pelaku dan kepentingan negara. Tegasnya, vonis yang dijatuhkan oleh hakim merupakan keseimbangan kepentingan antara kepentingan para pelaku di satu pihak serta kepentingan akibat dan dampak kesalahan yang telah diperbuat para pelaku di lain pihak. Konkritnya, penjatuhan pidana yang berlandaskan kepada asas monodualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Dengan demikian pemidanaan yang dijatuhkan hakim tersebut berlandaskan kepada eksistensi 2 (dua) asas fundamental yang dikenal dalam hukum pidana modern yaitu “asas legalitas” (yang merupakan asas 144 kemasyarakatan) dan “asas culpabilitas” atau asas kesalahan yang merupakan asas kemanusiaan/individual. Secara langsung ataupun tidak langsung, baik implisit maupun eksplisit maka putusan hakim tidak semata-mata bertumpu, bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) semata-mata karena apabila bertitik tolak demikian kurang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana. Pada hakikatnya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat non yuridis seperti aspek psikologis terdakwa, sosial ekonomis, agamis, aspek filsafat humanis, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek policy/filsafat pemidanaan, aspek disparitas pemidanaan, dan lain sebagainya maka hendaknya vonis diharapkan memenuhi dimensi keadilan. Konkretnya, putusan hakim juga mempertimbangkan aspek bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan adalah keadilan dengan orientasi pada moral justice, sosial justice dan legal justice. Pada hakekatnya, putusan hakim juga mengandung aspek pembalasan sesuai teori retributif, juga sebagai pencegahan (deterrence) dan pemulihan diri terdakwa (rehabilitasi). Dengan titik tolak demikian maka penjatuhan putusan yang dijatuhkan oleh hakim bersifat integratif dalam artian memenuhi aspek retributif, deterrence dan rehabilitasi. 4.2. Perumusan Sistem Sanksi Pidana Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana ada beberapa jenis sistem perumusan sanksi pidana (strafsoort), yaitu : 145 a. Sistem Perumusan Tunggal/ Imperatif Sistem perumusan jenis sanksi pidana /strafsoort bersifat tunggal/imperatif adalah sistem perumusan dimana jenis pidana dirumuskan sebagai satu-satunya pidana untuk delik yang bersangkutan. Untuk itu, sistem perumusan tunggal ini dapat berupa pidana penjara saja, kurungan saja ataupun juga pidana denda saja. Dilihat dari sudut penetapan jenis pidana, maka jenis perumusan tunggal ini merupakan peninggalan atau pengaruh yang sangat menyolok dari aliran klasik. Aliran ini ingin mengobjektifkan hukum pidana dari sifat-sifat pribadi si pelaku. Dengan sifatnya yang demikian, maka aliran ini pada awalnya timbulnya sama sekali tidak memberikan kebebasan kepada hakim untuk menetapkan jenis pidana dan ukuran pemidanaan.153 Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa sistem perumusan ancaman pidana tunggal jelas merupakan sistem definite sentence, khususnya dilihat dari sudut jenis pidana. Pada asasnya, sistem perumusan tunggal sebenarnya oleh kebijakan formulatif hendaknya harus dihindari karena sifatnya “imperatif”. Apabila dijabarkan lebih terperinci, maka sistem perumusan tunggal/imperatif mempunyai dimensi dimana kelemahan utamanya adalah bersifat sangat kaku karena bersifat “mengharuskan”. Aspek ini secara tajam diprediksi oleh Barda Nawawi Arief sebagai berikut : “Jadi hakim dihadapkan pada suatu jenis yang pasti “definite sentence“ dan sangat mekanik, karena mau tidak mau Hakim seolah-olah harus menetapkan pidana penjara secara otomatis. 153 Sudarto II, Op.cit, h. 55. 146 Hakim tidak diberi kesempatan dan kelonggaran untuk menentukan jenis pidana lain yang sesuai untuk terdakwa. Mengamati karakteristik yang demikian (yaitu bersifat “kaku, imperatif, difenite dan mekanik/otomatik”), jelas terlihat bahwa sistem demikian merupakan bukti dari adanya peninggalan atau pengaruh yang sangat menyolok dari aliran klasik. Sebagaimana dimaklumi aliran klasik ingin mengobjektifkan hukum pidana dari sifat-sifat subjektif si pelaku dan tidak memberi kebebasan kepada hakim untuk menetapkan jenis pidana dan ukuran pemidanaan.”154 Selanjutnya menurut Barda Nawawi Arief kelemahan lainnya dari sistem perumusan tunggal ialah : “Sulitnya menentukan ukuran yang rasional mengapa suatu tindak pidana itu hanya diancam dengan pidana penjara saja, sedangkan yang lainnya tidak. Mengapa misalnya untuk pencurian dan penggelapan (Pasal 362 dan 372 KUHP) diancam secara alternatif dengan pidana “penjara atau denda”, sedangkan untuk penipuan dalam Pasal 378 yang juga merupakan kejahatan terhadap harta benda hanya diancam dengan pidana penjara saja.155 Akan tetapi walaupun sistem perumusan tunggal mempunyai kelemahan utama tidaklah berarti sistem demikian tidak dapat diterapkan. Apabila sistem perumusan tunggal tetap digunakan, maka untuk menghindari sifat kaku tersebut tentu harus ada pedoman untuk hakim dalam hal menetapkan sistem perumusan tunggal itu menjadi lebih fleksibel, lunak dan elastis. Konkretnya adanya keleluasaan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara yang ditetapkan secara tunggal tersebut. Apabila dilihat pedoman yang demikian adanya penggantian dengan jenis pidana lain yang lebih ringan, sistem tunggal itu seolah-olah dapat diterapkan sebagai sistem alternatif, dan apabila hakim dapat menambah atau memperberat jenis pidana yang ditetapkan secara tunggal itu dengan 154 155 Barda Nawawi I, Op.cit, h. 259. Barda Nawawi I, Op.cit, h. 176. 147 jenis pidana lainnya sehingga seolah-olah sistem tunggal itu dapat juga diterapkan seperti sistem kumulatif. b. Sistem perumusan alternatif Dari aspek pengertian dan substansinya sistem perumusan alternatif adalah sistem dimana pidana penjara dirumuskan secara alternatif dengan jenis sanksi pidana lainnya berdasarkan urutan-urutan jenis sanksi pidana dari terberat sampai teringan. Dengan demikian hakim diberi kesempatan memilih jenis pidana yang dicantumkan dalam pasal bersangkutan. Pada umumnya perumusan alternatif bertitik tolak pada aspek : 1) hendaknya pemilihan jenis pidana tersebut berorientasi kepada “tujuan pemidanaan”, dan 2) hendaknya harus mengutamakan/ mendahulukan jenis pidana yang lebih ringan apabila pidana yang lebih ringan tersebut telah sesuai dengan tujuan pemidanaan. c. Sistem perumusan kumulatif Sistem perumusan kumulatif mempunyai ciri khusus yaitu adanya ancaman pidana dengan redaksional kata hubung “dan” seperti “pidana penjara dan denda”. Bila dianalisis lebih lanjut, sebenarnya sistem perumusan kumulatif identik dengan sistem perumusan tunggal karen a bersifat “imperatif”, sangat kaku dan “mengharuskan” hakim menjatuhkan pidana. Tegasnya, tidak ada kesempatan bagi hakim untuk memilih penerapan pidana yang dianggap paling cocok dengan perbuatan yang 148 dilakukan terdakwa karena hakim dihadapkan kepada jenis pidana yang sudah pasti (definite sentence). Walaupun demikian sistem perumusan kumulatif apabila dipertajam polarisasi pemikirannya ternyata juga mempunyai beberapa kebaikan, yaitu : 1) memberi kepastian hukum kepada terdakwa bahwa pemidanaannya mengacu kepada pidana kumulatif tersebut, dan 2) memberikan pidana yang lebih memberatkan kepada pelaku/ daders tindak pidana secara menggeneralisir tanpa melihat perbuatan tersebut kasus per kasus. d. Sistem perumusan kumulatif-alternatif Ditinjau dari terminologinya maka sistem perumusan kumulatif-alternatif mengandung dimensi-dimensi sebagai berikut : 1) Adanya dimensi perumusan kumulatif. Aspek ini merupakan konsekuensi logis materi perumusan kumulatif adanya ciri khusus kata “dan” di dalamnya; 2) Adanya dimensi perumusan alternatif di dalamnya 3) Adanya dimensi perumusan tunggal di dalamnya Aspek ini tercermin dari sistem perumusan kumulatif-alternatif dengan adanya kata “dan/atau”. Dari konteks ini adanya eksistensi perumusan tunggal dimana pada kebijakan aplikatifnya hakim dapat/ harus memilih salah satu jenis pidana tersebut. Sistem perumusan ini paling banyak yang memuat ancaman pidana “penjara dan/atau denda”. Apabila diperbandingkan dengan sistem 149 perumusan yang terdahulu nampaknya kumulatif-alternatif ini relatif cukup significant, yaitu : a. Bahwa sistem perumusan kumulatif-alternatif secara substansial juga meliputi sistem perumusan tunggal, kumulatif dan alternatif sehingga dengan eksplisit dan implisit telah menutupi kelemahan masing-masing sistem perumusan tersebut. b. Bahwa sistem perumusan kumulatif-alternatif merupakan pola sistem perumusan yang secara langsung adalah gabungan bersirikan nuansa kepastian hukum (rechts-zekerheids) dan nuansa keadilan; dan c. Karena merupakan gabungan antara nuansa keadilan dan kepastian hukum (rechts-zekerheids) maka cirri utama sistem perumusan ini di dalam kebijakan aplikatifnya bersifat fleksibel dan akomodatif. Untuk itu, guna rekomendasi pada kebijakan formulatif/legislatif masa mendatang atau sebagai ius constituendum di kemudian hari hendaknya pembentuk undang-undang lebih baik membuat sistem perumusan yang bersifat kumulatif-alternatif. Ilmu pengetahuan Hukum Pidana juga mengenal ampat sistem perumusn lamanya sanksi pidana (strafmaat) yaitu : a. Sistem fixed/definite sentence berupa ancaman pidana yang sudah pasti. b. Sistem indefinite sentence berupa ancaman lamanya pidana secara maksimum. c. Sistem indeterminate sentence berupa tidak ditentukan batas maksimum pidana sehingga badan pembuat umdang-undang menyerahkan sepenuhnya 150 kebijakan (diskresi) pidana kepada aparat pelaksana pidana yang berada pada tingkatan yang lebih rendah, misalnya dalam menetapkan ukuran, sifat atau lamanya pidana untuk pelaku kejahatan tertentu. d. Sistem determinate sentence berupa ditentukannya batas minimum/maksimum lamanya ancaman pidana. Kebijakan formulatif terhadap jenis sistem perumusan sanksi pidana (strafsoot) dan perumusan lamanya sanksi pidana (strafmaat) tersebut akhirnya bermuara pada bagaimana cara pelaksanaan pidana (strafmodus), jadi dari sudut sistem pembinaannya (treatment) dan kelembagaannya/institusinya. Sebelum UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT diberlakukan, penegak hukum mempergunakan Pasal 356 KUHP untuk menjerat pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Pasal tersebut menyatakan : Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah sepertiganya : 1e. jika si pelaku melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapaknya yang sah, isterinya (suaminya) atau anaknya. Sedangkan Pasal 351 KUHP menentukan: 1) penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 135.000,2) jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si pelaku dipidana penjara selama-lamanya 5 tahun 3) jika perbuatan itu menjadikan korbannya mati, maka pelaku dipidana penjara selama-lamanya 7 tahun 4) dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja 5) percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum. 151 Melihat kepada bunyi ayat (4) pasal di atas, harus ditafsirkan bahwa perbuatan apa pun yang dilakukan seseorang, baik itu memukul, menendang, menampar, dan lain-lain yang dapat mengakibatkan rusaknya kesehatan seseorang, harus dianggap sebagai penganiayaan. Pada implementasinya, UUPKDRT menggunakan sistem perumusan alternatif berupa ancaman pidana penjara atau denda. Bentuk perumusan ini terdapat dalam bab VIII (Pasal 44 (kekerasan fisik), Pasal 45 (kekerasan psikis), Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 (kekerasan seksual), serta Pasal 49 (penelantaran). Pasal 44 UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menentukan : 1) setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau dengan denda paling banyak Rp 15.000.000,-. 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,-. 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,-. 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau 152 kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,Pasal 45 UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menentukan : 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Ketentuan tentang kekerasan psikis ini ancaman pidananya lebih ringan dibandingkan ketentuan-ketentuan kekerasan lainnya dalam lingkup rumah tangga. Padahal akibat yang ditimbulkan dari kekerasan psikis ini sama beratnya dengan kekerasan fisik karena berkaitan dengan harga diri walaupun kekerasan psikis ini tidak meninggalkan luka pada fisik sehingga sulit untuk dilihat dengan mata telanjang. Tetapi kekerasan psikis dapat menimbulkan stres pada korban, dari stres inilah dapat membuat tubuh menjadi lemah sehingga mudah jatuh sakit. Pasal 46 UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menentukan : Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 153 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Pasal 47 UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menentukan : Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Pasal 48 UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menentukan : Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 49 UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menentukan : Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: 154 a) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); b) Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2). Dalam hal penelantaran ini tidak dijelaskan perbedaan sanksi pidana terhadap penelantaran ekonomi atau penelantaran nafkah lahir dan batin. Apabila penelantaran yang terjadi adalah hanya penelantaran ekonomi maka penjatuhan sanksi pidana penjara tidaklah tepat, akan lebih baik jika pidana yang dijatuhkan berupa pidana denda dengan batas minimum dan maksimum serta ganti kerugian terhadap korban yang ditelantarkan. Jadi korban pun merasa haknya dipenuhi oleh hukum. Keputusan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku sepenuhnya ada di tangan hakim. Apabila dikaji lebih dalam terhadap UUPKDRT yang menganut rumusan pidana alternatif berupa pidana penjara atau denda, bisa jadi hakim memutuskan dengan menjatuhkan pidana denda saja. Adanya pilihan ini akan sangat menguntungkan pelaku, sehingga pelaku tidak perlu menjalani pidana penjara dalam kurun waktu tertentu. Pelaku masih bebas berkeliaran dan besar kemungkinan timbul rasa tidak aman dan tidak nyaman bagi korban. Sedangkan pencantuman ancaman pidana maksimal saja memberikan peluang bagi pelaku mendapat sanksi pidana yang rendah karena ketiadaan batasan minimal. Bagian akhir dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini memuat tentang ketentuan pidana, dengan beberapa bentuk 155 pidana yakni pidana penjara, pidana denda dan pidana pengawasan. Besarnya pidana penjara dan denda ada dalam rentang satu tahun sampai dengan lima belas tahun, yang nampaknya mengacu pada ketentuan dalam KUHP, karena parameter penetapan pidana ini sama sekali tidak pernah diuraikan, seperti juga dalam peraturan-peraturan lainnya. Suatu parameter bagi penetapan sanksi pidana baru dapat diciptakan apabila telah disepakati sebelumnya apa yang hendak dijadikan landasan berpikir untuk pemidanaan. Berkenaan dengan parameter penentuan pidana, Tim Perumus KUHP telah membuat peringkat berdasar keseriusan (gravity) tindak-tindak pidana. Peringkat ini dibagi ke dalam lima tingkat dengan menggunakan tehnik skala semantic, dari “sangat ringan” sampai dengan “sangat serius“ dengan catatan bahwa tindak pidana yang “sangat ringan“ tidak dikenakan perampasan kemerdekaan, sedang tindak pidana yang sangat serius adalah tindak pidana yang dikenai sanksi pidana penjara lebih dari tujuh tahun. Sangat disayangkan konstruksi skala ini tidak dikembangkan lebih lanjut. Oleh karenanya lagi-lagi dijumpai masalah dalam menetukan proporsi masing-masing tindak pidana, baik dalam hal paritas, peringkat maupun jarak kualitatif (parity, rank-ordering and spacing) antara satu tindak pidana dengan yang lain. Tidak dijelaskan tentang cara Tim Perumus menentukan kategori tindak pidana, tapi nampaknya belum ditemukan metode tertentu sehingga klasifikasi, peringkat dan penentuan sanksi pidana masih mirip dengan KUHP, seperti juga yang ditemukan dalam UU PKDRT. Upaya menentukan proporsi ini memang sama sekali tidak mudah, akan tetapi sangat penting demi konsistensi, bukan hanya dalam tingkat legislasi tetapi 156 juga pada tingkat implementasi oleh lembaga yudikatif kelak. Erat kaitannya dengan ini adalah parameter pemidanaan dalam perumusan sanksi. Barda Nawawi dan Soedarto sudah mengeluhkan kondisi semacam ini. Dapat dipastikan ketiadaan parameter ini bukan sekedar masalah tehnis, tapi juga masalah filosofis, sehubungan dengan tidak adanya falsafah pemidanaan. Kondisi ini diperberat lagi karena proses legislasi sebagai suatu proses politik yang menghasilkan hukum yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia, sampai saat ini memang belum memuaskan. Adanya logrolling atau vote trading, cukup banyak memberi warna pada proses ini. Selain itu, mekanisme penggodokan yang sampai kini masih diperdebatkan, rendahnya partisipasi publik, dan kemampuan para legislator sendiri merupakan faktor yang paling signifikan dalam menentukan kualitas produk legislatif. Hal ini makin terasa ketika melihat produk hukum pidana, karena proses ini pada dasarnya merupakan suatu proses politik dengan argumenargumen politik. Untuk menentukan perilaku yang dipandang layak diancam dengan sanksi pidana, dan kemudian, jenis dan besaran pidana yang layak diancamkan pada perilaku tersebut. Penentuan perilaku yang dirumuskan sebagai tindak pidana seharusnya diawali dengan pertanyaan : apakah suatu perilaku selayaknya diserahkan pada private ethics ataukah ia telah menjadi bagian dari ranah (domain) publik. Mayoritas warga termasuk para ahli hukum cenderung untuk bersikap menerima begitu saja perilaku yang dirumuskan sebagai tindak pidana beserta sanksi pidananya, yang dapat didasarkan hanya atas informed acceptance maupun indifference. Apakah ini mencerminkan kepercayaan mutlak 157 mereka pada lembaga legislatif, atau ketidaktahuan masyarakat, belum pernah diteliti. Ada beberapa hal yang patut menjadi pemikiran bersama dari persfektif teori pemidanaan dan tujuan diberlakukannya UU PKDRT. Hal-hal tersebut adalah : a) Penerapan pidana penjara jangka pendek dalam hal ini tidaklah akan memberi dampak positip apa pun, bahkan menimbulkan dampak negatif seperti stigma pada pelaku, pengaruh buruk dari sesama napi di LP, rusaknya hubungan perkawinan, dan akibat lain terhadap anak dalam keluarga yang mengalami KDRT tersebut. Eksistensi pidana penjara jangka pendek sudah lama dipertanyakan dalam kajian hukum pidana, karena lebih banyak dampak negatif daripada tujuan yang bisa dicapai. b) Jika hakim memang mempertimbangkan berbagai hal yang sifatnya meringankan pada diri pelaku, maka sebaiknya hakim menerapkan sanksi pidana bersyarat, yang tidak berdampak negatif sama sekali. Bahkan dalam hal ini hakim dapat memberikan syarat-syarat tertentu yang justru dapat mencegah pelaku mengulangi perbuatan KDRT. Hakim misalnya dapat mensyaratkan bahwa pelaku tidak boleh berkata atau bersikap kasar kepada korban, atau melakukan penelantaran rumah tangga selama masa percobaan tersebut, atau mensyaratkan pelaku untuk menjalani konseling khusus dalam mengatasi perilaku kekerasan tersebut. Melihat uraian ini memang upaya penentuan sanksi pidana harus sudah dimulai melalui suatu penelitian yang mendalam untuk menjaring pandangan dan 158 dinamika masyarakat, serta nilai-nilai yang berkembang di dalamnya. Hanya dengan cara itulah maka akan diperoleh suatu gambaran yang akurat mengenai penentuan sanksi pidana dalam berbagai ketentuan pidana kita, termasuk KDRT. 4.3. Kajian Perbandingan dengan Negara Lain Dalam bulan Februari 2006, Pemerintah Australia telah mengeluarkan Family Law Violence Strategy. Strategi tersebut membentuk bagian tambahan pada perubahan-perubahan hukum keluarga Pemerintah Australia. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan cara penanganan kasus-kasus dan tuduhan kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan anak dalam sistem hukum keluarga. Strategi meliputi penelitian tentang bagaimana pengadilan-pengadilan menangani tuduhan kekerasan dalam rumah tangga. Strategi tersebut juga akan menyelidiki bagaimana menyempurnakan proses-proses pengadilan untuk kasuskasus yang melibatkan kekerasan dan akan memungkinkan Family Law Council untuk mempertimbangkan penyempurnaan cara-cara penanganan kasus-kasus tersebut. Strategi menanggulangi kepedulian Pemerintah bahwa tuduhan kekerasan dan pelecehan harus diinvestigasi oleh instansi negara bagian dan wilayah yang bersangkutan sesegera mungkin.156 The Australian Family Law Act has remained ambivalent as to how domestic violence is to be understood in relation to parenting. In part, this may be influenced by the contradictions inherent in considering what is in the best interests of the child along with the conflicting rights of the child under the UN Convention in cases of domestic violence.157 156 157 http://www.scribd.com/doc/40969125/Kekerasan-Dalam-Rumah-Tangga Anastasia Powell And Suellen Murray, 2008, Children and Domestic Violence : Constructing A Policy Problem in Australia and New Zealand, SAGE Publications, Melbourne, h. 467. 159 Tindakan hukum keluarga di Australia tetap ambivalen seperti bagaimana kekerasan dalam rumah tangga adalah untuk dimengerti dalam kaitannya terhadap hubungan dengan orang tua. Dalam hal ini mungkin dipengaruhi oleh kontradiksi yang melekat dalam mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sepanjang bertentangan dengan hak-hak anak pada Konvensi PBB dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pengaturan tentang KDRT di Negara lain tidak diatur secara khusus dalam suatu undang-undang yang spesifik dan tidak membatasi locus delictinya, namun yang tampak bahwa suatu pengaturan mengatur suatu tindak pidana yang berkaitan dengan KDRT hanya karena hubungan dengan korban. Beberapa tindak pidana yang tersebut adalah yang berkaitan dengan kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan penelantaran, antara lain158 : 1. KUHP Bulgaria Pasal 115 mengatur pembunuhan biasa, diancam pidana perampasan kemerdekaan (deprivation of liberty) 10 (sepuluh) tahun sampai 20 ( dua puluh) tahun. Namun, apabila dilakukan oleh orang tertentu dalam keadaan tertentu terhadap ayah/ ibu atau anaknya sendiri, wanita hamil, dll, ancaman pidananya diperberat menjadi 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) tahun perampasan kemerdekaan atau seumur hidup atau mati sebagaimana diatur dalam Pasal 116. 2. KUHP Perancis 158 Barda Nawawi Arief, 2005, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 61-68. 160 Menurut Artikel 221-1, pembunuhan (murder) diancam pidana 30 (tiga puluh) tahun. Apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap keluarga/ orang tuanya sendiri atau ayah dan ibu angkatnya (a natural or legitimate ascendant or the adoptive father or mother), ancaman pidananya diperberat menjadi penjara seumur hidup. Pemberatan pidana ini hanya berlaku pada tindak pidana pembunuhan, tetapi juga berlaku pada tindak pidana penganiayaan (torture) sebagaimana diatur dalam Artikel 222-3 dan tindak pidana kekerasan (violence) yang diatur dalam Artikel 222-8 (violence causing intended death), Artikel 222-10 (violence causing mutilation or permanent disability), Artikel 222-12 (violence causing a total incapacity to work for more than eight days), dan artikel 222-13 (violence causing an incapacity to work of eight days or less). 3. KUHP Korea Pasal 250 ayat (1) mengatur tentang pembunuhan biasa dengan ancaman pidana mati, penjara kerja paksa seumur hidup, atau penjara tidak kurang dari 5 (lima) tahun. Sedangkan pada ayat (2) yang lebih dikenal dengan istilah Killing an Ascendant, apabila tindak pidana dilakukan terhadap keluarga / orang tua garis lurus ke atas (lineal ascendant) dari pihak si pelaku atau pihak istri atau suaminya, diancam dengan pidana mati atau penjara kerja paksa seumur hidup. Tindak Pidana terhadap lineal ascendant ini juga berlaku terhadap beberapa tindak pidana lainnya seperti : - Penganiayaan dan kekerasan (crimes of bodily injury and violence) diatur pada Pasal 257:2, 258:2, 259:2, dan 260:2; 161 - Kejahatan menelantarkan (crimes of abandonment) yang diatur pada Pasal 271:2, termasuk juga di dalamnya tindakan perlakuan kejam (cruelty treatment) sebagaimana diatur dalam Pasal 273:2; - Penahanan/pengurungan/perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (false arrest and false imprisonment) diatur pada Pasal 276:2 dan 277:2; - Kejahatan intimidasi/pengancaman (crimes of intimidation) diatur pada Pasal 283:2. 4. KUHP Jepang Objek tindak pidana sama dengan KUHP Korea, yaitu terhadap orang tua garis lurus ke atas baik dari pihak suami atau pun istri. Ini jelas menunjukkan, perwujudan dari nilai budaya “penghormatan, penghargaan, dan perlindungan martabat orang tua/leluhur” di Jepang dan Korea. Tindak pidana terhadap a lineal ascendant (of the offender or his/her spouse) ini meliputi : - Pasal 200 tentang pembunuhan; - Pasal 205 ayat (2) tentang penganiayaan; - Pasal 218 ayat (2) tentang penelantaran; - Pasal 220 ayat (2) penahanan/pengurungan melawan hukum; dan - Pasal 222 ayat (2) tentang pengancaman terhadap keluarganya termasuk orang tuanya. 5. KUHP Singapore dan Malaysia 162 Pada Bab XVI tentang offences Affecting the Human Body Pasal 317, diatur tentang meninggalkan atau menelantarkan anak di bawah 12 (dua belas) tahun (abandonment of a child under twelve years). 6. KUHP Polandia - Bab 22 offences Againts Liberty Pasal 170 tentang perbuatan tidak senonoh dengan menyalahgunakan hubungan ketergantungan; - Bab 23 offences Againts Decency Pasal 175 tentang hubungan seksual dalam hubungan keluarga atau dalam hubungan adopsi. 7. KUHP Yugoslavia Bab XVI Criminal Offences Againts the Dignity of the Person and Morals Pasal 183 diatur tentang persetubuhan yang menyalahgunakan kedudukan dalam hubungan subordinasi/ketergantungan sebagai guru, pendidik, pembimbing, orang yang mengadopsi, ayah tiri. 8. KUHP Norwegia Untuk delik kesusilaan, diatur dalam Bab XIX Offences Againts Public Moral yang meliputi : - Perbuatan yang berkaitan dengan hubungan tidak senonoh (indecent relations) dengan ancaman pidana berkisar antara 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) tahun penjara. Perbuatan tidak senonoh yang menyalahgunakan hubungan ketergantungan jabatan/kedudukan atau hubungannya dengan korban diatur pada Pasal 198-199; - Perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan hubungan tidak senonoh dengan membujuk atau dengan tipu muslihat sebagaimana diatur 163 dalam Pasal 200 ditentukan sebagai berikut : “Public prosecution shall be initiated only on request of the victim, unlessrequiredin the public interest”. Selain atas dasar pengaduan korban, penuntutan juga dapat dilakukan atas dasar kepentingan umum sekalipun tanpa pengaduan. Jadi, relativitas pengaduan tidak semata-mata digantungkan pada kepentingan individu/korban, tetapi juga kepentingan umum. - Perbuatan melakukan hubungan seksual (sexual intercourse) yang dilakukan dengan keluarga garis lurus ke bawah/ ke atas (incest) sebagiamana diatur pada Pasal 207. Pada umumnya Negara lain tidak mengatur secara khusus tentang kekerasan dalam rumah tangga. Ketentuan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam KUHP dengan ancaman pidana yang sangat berat seperti tentang pengaturan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan fisik sampai pada perampasan kemerdekaan (Bulgaria, Perancis, Korea, dan Jepang), delik asusila (Polandia, Yugoslavia, dan Norwegia) dan tentang penelantaran rumah tangga (Korea, Singapore dan Malaysia). Ada hal unik yang dapat dijadikan bahan pemikiran dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia adalah penentuan delik aduan atas delik asusila di Norwegia tidak bersifat delik aduan absolut tetapi lebih cenderung ditentukan sebagai delik aduan relatif demi kepentingan umum sehingga apabila suatu tindak pidana telah mengancam keamanan dan ketertiban umum, tidak terbatas pada korban saja, maka suatu tindak pidana tetap dapat diproses menurut hukum sebagai bentuk tanggung jawab Negara untuk melindungi warga negaranya. 164 BAB V PENUTUP 5.1. Simpulan a. Kebijakan formulatif terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut ketentuan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) pada beberapa ketentuan pasalnya yang tidak menimbulkan akibat yang berupa penyakit atau halangan untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari ditentukan sebagai delik aduan sebagaimana tersebut pada Pasal 51 (kekerasan fisik), 52 (kekerasan 165 psikis), dan 53 (kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami atau istri). Delik aduan yang menitik beratkan pada pengaduan korban memiliki kelemahan yang mengakibatkan tidak semua pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat dijerat hukum. Para pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat saja bebas dari segala tuntutan hukum apabila korbannya tidak membuat pengaduan atau mencabut pengaduannya padahal perbuatan pelaku jelas-jelas melanggar hak asasi korban. Diperlukan pengaturan yang lebih tegas dalam UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga mengenai klasifikasi perbuatan mana saja yang termasuk delik aduan dan perbuatan yang termasuk delik biasa. b. Kebijakan hukum pidana dalam perumusan sistem sanksi pidana terhadap tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut ketentuan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) menggunakan jenis sistem perumusan alternatif. Pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara atau denda dengan aturan minimum dan maksimum. Dalam Pasal 44 (kekerasan fisik), Pasal 45 (kekerasan psikis), dan Pasal 49 (penelantaran) tidak ditentukan batas minimal pidana hanya menyebut batas maksimal saja. Sedangkan untuk Pasal 46 dan Pasal 47 tentang kekerasan seksual disebutkan dalam Pasal 48 ditentukan dengan jelas batas minimal dan batas maksimal penjatuhan pidana penjara dan pidana dendanya. Ancaman pidana bersifat alternatif, keputusan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku sepenuhnya ada di tangan hakim. 166 Namun dengan adanya ketentuan ancaman pidana yang bersifat alternatif, bisa jadi hakim memutuskan dengan menjatuhkan pidana denda. Hal ini akan sangat menguntungkan pelaku karena tidak perlu menjalani pidana penjara dalam kurun waktu tertentu. Pelaku masih bebas berkeliaran dan besar kemungkinan timbul rasa tidak aman dan tidak nyaman bagi korban. Selain itu ketentuan tentang kekerasan psikis ancaman pidananya lebih ringan dibandingkan ketentuan-ketentuan kekerasan lainnya dalam lingkup rumah tangga. Padahal akibat yang ditimbulkan dari kekerasan psikis ini sama beratnya dengan kekerasan fisik karena berkaitan dengan harga diri walaupun kekerasan psikis ini tidak meninggalkan luka pada fisik sehingga sulit dilihat oleh mata. 5.2. Saran a. Perlu kajian ulang terhadap Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti kriminalisasi atas suatu perbuatan, sifat delik aduan pada beberapa tindak pidana karena ada beberapa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang lebih tepat bila termasuk dalam delik biasa demi perlindungan Hak Asasi Manusia dan tegaknya keadilan. b. Selain sanksi maksimal perlu pencantuman lebih tegas dalam hal batas minimal penjatuhan sanksi pidana baik penjara maupun denda untuk adanya jaminan kepastian hukum, serta sifat alternatif sanksi dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga perlu 167 dipertimbangkan untuk menggunakan sistem kumulatif-alternatif karena apabila menggunakan sistem alternatif saja untuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang tergolong berat sangatlah tidak adil bagi korban, dimana pelaku dapat bebas dari pidana penjara hanya dengan membayar denda saja, sehingga korban merasa tidak aman.