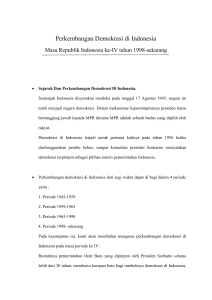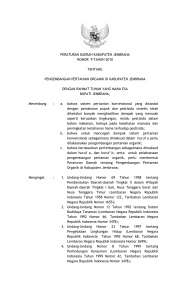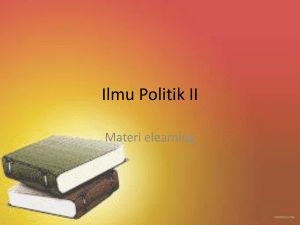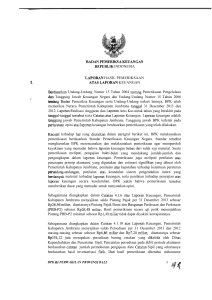bab i menguak dimensi kekuasaan dalam reformasi
advertisement
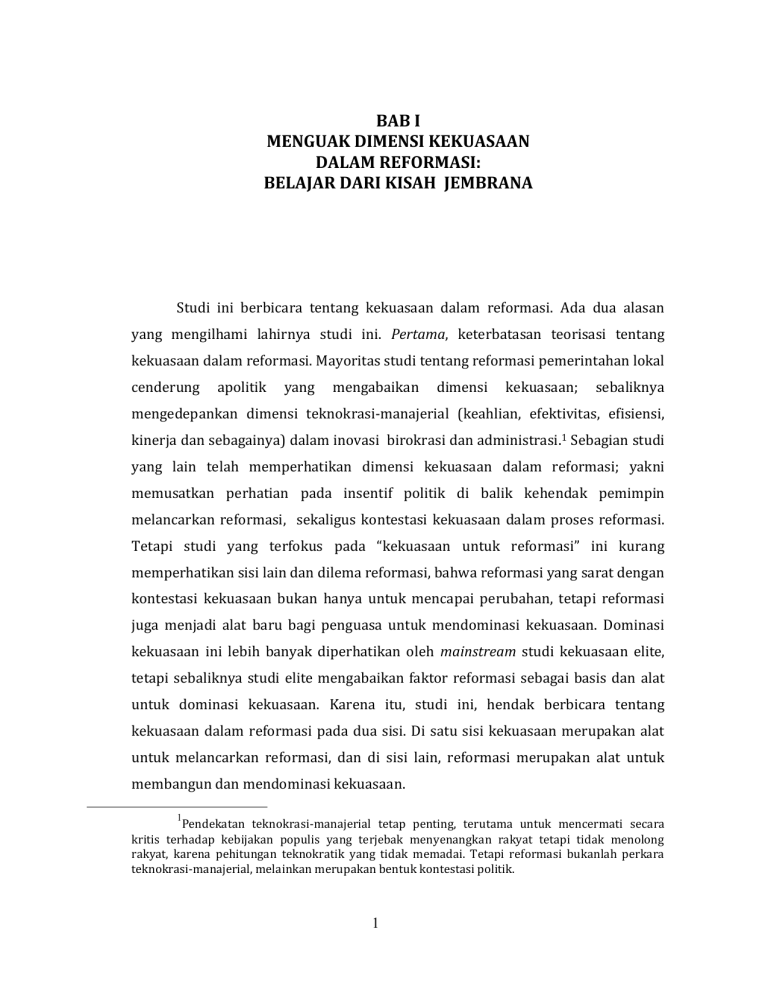
BAB I MENGUAK DIMENSI KEKUASAAN DALAM REFORMASI: BELAJAR DARI KISAH JEMBRANA Studi ini berbicara tentang kekuasaan dalam reformasi. Ada dua alasan yang mengilhami lahirnya studi ini. Pertama, keterbatasan teorisasi tentang kekuasaan dalam reformasi. Mayoritas studi tentang reformasi pemerintahan lokal cenderung apolitik yang mengabaikan dimensi kekuasaan; sebaliknya mengedepankan dimensi teknokrasi-manajerial (keahlian, efektivitas, efisiensi, kinerja dan sebagainya) dalam inovasi birokrasi dan administrasi.1 Sebagian studi yang lain telah memperhatikan dimensi kekuasaan dalam reformasi; yakni memusatkan perhatian pada insentif politik di balik kehendak pemimpin melancarkan reformasi, sekaligus kontestasi kekuasaan dalam proses reformasi. Tetapi studi yang terfokus pada “kekuasaan untuk reformasi” ini kurang memperhatikan sisi lain dan dilema reformasi, bahwa reformasi yang sarat dengan kontestasi kekuasaan bukan hanya untuk mencapai perubahan, tetapi reformasi juga menjadi alat baru bagi penguasa untuk mendominasi kekuasaan. Dominasi kekuasaan ini lebih banyak diperhatikan oleh mainstream studi kekuasaan elite, tetapi sebaliknya studi elite mengabaikan faktor reformasi sebagai basis dan alat untuk dominasi kekuasaan. Karena itu, studi ini, hendak berbicara tentang kekuasaan dalam reformasi pada dua sisi. Di satu sisi kekuasaan merupakan alat untuk melancarkan reformasi, dan di sisi lain, reformasi merupakan alat untuk membangun dan mendominasi kekuasaan. 1 Pendekatan teknokrasi-manajerial tetap penting, terutama untuk mencermati secara kritis terhadap kebijakan populis yang terjebak menyenangkan rakyat tetapi tidak menolong rakyat, karena pehitungan teknokratik yang tidak memadai. Tetapi reformasi bukanlah perkara teknokrasi-manajerial, melainkan merupakan bentuk kontestasi politik. 1 Kedua, studi ini diilhami oleh pengalaman pergulatan kekuasaan dan reformasi di Kabupaten Jembrana selama dipimpin oleh Bupati I Gede Winasa (IGW). Jembrana telah menjadi ikon dan teladan reformasi pemerintahan daerah. Bupati IGW meraih kejayaan ganda (reformasi dan kekuasaan), tetapi reformasi dan kekuasaan itu berakhir dengan keruntuhan secara dramatis. Penulis hendak mendialogkan antara narasi besar (kekuasaan dalam reformasi) dengan narasi kecil (pengalaman Jembrana) itu. Dengan kalimat lain, studi ini mengkaji kekuasaan dalam reformasi yang bekerja secara kontekstual di Jembrana. Narasi kecil Jembrana tentu telah memberi ilham besar bagi penulis untuk menantang narasi besar kekuasaan dalam reformasi. Jembrana menjadi medan studi dan medan dialektika antara narasi kecil dan narasi besar, sekaligus menjadi modalitas untuk membangun teori alternatif tentang dua sisi kekuasaan dalam reformasi, yakni kekuasaan sebagai alat reformasi dan reformasi sebagai alat kekuasaan. A. Latar Belakang Negara, Jembrana, 16 November 2010. Barisan massa Forum Daerah (Forda) LSM meruntuhkan dan membakar (ngaben) patung besar I Gede Winasa (IGW) di RSUD Negara, sehari sesudah sang bupati itu turun dari tahta. Mereka bersama pihak RSUD kemudian mengantar patung yang telah dibakar itu dengan ambulance sampai ke rumah IGW di Kelurahan Tegalcangkring, Mendoyo. Tindakan politik simbolik itu merupakan sebuah akumulasi panjang setelah bertahun-tahun kekuatan aksi kolektif (Jaringan Anti Korupsi, Forda LSM, Jembrana Forum, Komunitas Warga Jembrana Antikorupsi, dan lain-lain) melakukan perlawanan terhadap praktik-praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) yang dilakukan Bupati IGW dan teman-temannya. Dedengkot LSM Jembrana, Ketut Sujana, yang mempunyai jaringan luas secara nasional, memperoleh dua ilham ketika merobohkan dan membakar patung IGW. Pertama, patung bagi orang Bali merupakan simbol yang sakral. Forda LSM menganggap 2 patung IGW merupakan simbol terakhir kekuasaan IGW. "Ini merupakan pukulan terakhir terhadap kekuasaan yang korup dan penuh kebohongan," ujar Ngurah Karyadi, seorang aktivis Forda LSM (Antara News, 17 November 2010; Bali Post, 19 November 2010). Kedua, tindakan masyarakat sipil prodemokrasi yang meruntuhkan patung-patung Stalin di Uni Soviet dua dekade silam setelah gerakan mereka memenangkan pertarungan atas totalitarianisme. Aksi LSM itu merupakan bentuk delegitimasi IGW di saat dia tengah memromosikan anak sulungnya, I Gede Ngurah Patriana Krisna, bersama dengan Ketut Subanda, untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati dalam pilkada langsung Desember 2010. Mereka secara lantang menyerukan “Jangan Pilih Anak Koruptor” sebagai bentuk negative campaign untuk mengalahkan pasangan I Gede Ngurah Patriana Krisna dan Ketut Subanda yang didukung Partai Demokrat dan IGW. Pada saat yang sama mereka mendukung pasangan Putu Artha-Kembang Hartawan (Wakil Bupati dan Ketua DPRD Jembrana) yang didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pertarungan pilkada langsung 27 Desember 2010 membuahkan kemenangan kubu Putu Artha-Kembang Hartawan, sekaligus kekalahan dan kegagalan IGW dalam membangun dinasti politik. Hari-hari setelah kelengseran dan kegagalan IGW, pihak kepolisian dan kejaksaan – yang memperoleh endorsement Gubernur Bali Mangku Pastika – melakukan penyidikan secara intensif terhadap IGW yang sejak April 2009 diduga kuat terlibat dalam kasus korupsi sebesar Rp 2,3 M dalam pabrik kompos di Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Jembrana. Pada tanggal 19 Januari 2011, IGW secara resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri di rumah tahanan. Di penjara, Winasa bertemu dengan Nyoman Suryadi (mantan Kadis PULH) Jembrana, Nyoman Gede Sadguna (PPTK), IGK Muliarta (Mantan Direktur Perusda) Jembrana dan Agung Permadi (Direktur CV Puri Bening). Mereka saling berangkulan, dan Suryadi dengan nada prihatin berujar: “Akhirnya kita bertemu di sini”. Para kerabat dan para pendukungnya tentu sangat prihatin dengan peristiwa yang tragis itu, sebab 3 menurut mereka, Winasa ketika berkuasa, telah membuktikan sebagai bupati yang benar-benar pro rakyat. Meskipun pada awal Juli 2011 Pengadilan Negeri Negara memutus bebas IGW, tetapi rentetan cerita kekalahan dan kegagalan IGW di penghujung kekuasaannya, memberikan pertanda delegitimasi terhadap IGW dan kemerosotan reformasi. Kementerian Dalam Negeri maupun Gubernur Bali Mangku Pastika mengingatkan kepada Bupati dan Wakil Bupati baru agar menghentikan proyekproyek mercusuar warisan IGW, menjalankan inovasi pemerintahan yang sesuai dengan regulasi dan menjalankan agenda kebijakan yang sejalan dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Bali. Permintaan ini diindahkan oleh penguasa baru, Putu Artha dan Kembang Hartawan, yang menghentikan berbagai kebijakan unggulan dan proyek mercusuar warisan (legacy) IGW. Meskipun penguasa baru belum memiliki paradigma alternatif dalam pengelolaan pemerintahan, tetapi paradigma efisiensi DOA (dana, orang dan alat) yang dibangun IGW, dihentikan dengan cara menata kembali struktur birokrasi daerah. Karya besar IGW, Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ), yang digunakan untuk menopang kesehatan gratis, telah mengalami krisis finansial dan krisis kepercayaan dari para tenaga kesehatan sejak pertengahan 2010, dan kemudian dihentikan oleh penguasa baru pada bulan Februari 2011. Bupati Putu Artha, yang didukung DPRD, mengambil keputusan untuk mengintegrasikan JKJ ke dalam JKBM (Jaminan Kesehatan Bali Mandara) milik Provinsi Bali, mulai tahun 2012. Keruntuhan IGW dan krisis reformasi warisan IGW pada tahun 2010 sungguh kontras jika dibandingkan dengan kejayaan tahun-tahun sebelumnya. Jembrana, di bawah pimpinan Bupati IGW, adalah perintis reformasi kebijakan sekolah dan kesehatan gratis sejak 2001, serta reformasi birokrasi yang membuat birokrasi menjadi lebih ramping, efisien, bersih dari korupsi dan disiplin sejak 2003/2004. IGW mampu menyulap gedung-gedung Pemda -- yang sempat dibakar massa pada saat Megawati kalah bertarung melawan Abdurrahman Wahid dalam pemilihan presiden di MPR pada Oktober 1999 – menjadi lebih bagus dan megah; 4 membangun kembali Pura Jagat Natha sebuah pura besar yang menjadi simbol religiusitas masyarakat Hindu Bali; juga mampu menyulap kawasan rawa-rawa kota Negara menjadi lebih bersih, rapi, indah, hijau dan manusiawi. Jembrana menjadi lebih maju dan terkenal. Penghargaan dan pujian kepada Jembrana dan secara khusus kepada sang bupati IGW mengalir dari berbagai pihak, termasuk rakyat Jembrana sendiri. Majalah nasional terkemuka, Tempo, pada akhir tahun 2004 memberikan anugerah “The Man of The Year” kepada IGW karena ia dinilai sebagai pemimpin daerah yang telah sukses membawa perubahan besar dan bermanfaat bagi rakyat. Sepanjang 2004-2009 sudah lebih dari seribu kunjungan untuk mempelajari rahasia “cerita sukses” Jembrana. Kecuali daerah-daerah tetangganya di Bali, hampir semua daerah di Indonesia telah datang belajar ke Jembrana, mempelajari resep reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Para pejabat Jakarta, aktivis NGOs, peneliti dalam negeri dan mancanegara, maupun lembaga-lembaga donor juga mempelajari kisah sukses Jembrana. Yayasan Tifa, misalnya, pada tahun 2005 meneliti dan memublikasikan sebuah buku kecil bertitel “Semua Bisa Seperti Jembrana”, yang diharapkan menjadi bahan pembelajaran dan percontohan inovasi pemerintahan daerah. Kemendagri dan Kemenpan juga menjadikan Jembrana sebagai teladan reformasi birokrasi pemerintahan daerah untuk bisa dicontoh oleh daerah-daerah lain di Indonesia. Tetapi setelah IGW runtuh dan reformasi mengalami krisis, Jembrana tidak lagi menjadi “teladan” reformasi. Jembrana pasca-IGW kembali menjadi daerah yang “biasa” seperti daerah-daerah lainnya. Banyak pihak dari luar Jembrana, termasuk para peneliti dan promotor Jembrana, mempunyai pertanyaan besar, mengapa karya reformasi yang gemilang bisa berhenti secara bersamaan dengan keruntuhan sang bupati. Tentu kisah paradoks Jembrana itu sangat menarik dan menantang bagi studi politik lokal, baik studi tentang pergulatan kekuasaan maupun studi tentang perubahan (reformasi). Di satu sisi kisah Jembrana tidak cukup dilihat dari cara 5 pandang reformasi (perubahan) semata meskipun reformasi merupakan realitas dan ikon utama Jembrana. Pertama, studi reformasi pada umumnya, termasuk studi reformasi Jembrana (Eko Prasojo, 2005; Ketut Putra Erawan, 2007; R. Nugroho, 2008), hanya melihat dari sisi kepemimpinan dan manajerial yang membawa perubahan, namun abai terhadap dimensi pergulatan kekuasaan. Seolah-olah reformasi berjalan di ruang yang hampa politik, baik politik sebagai instrumen atau kekuatan untuk menjalankan reformasi maupun politik sebagai akibat reformasi. Kedua, studi reformasi cenderung mengabaikan dilema reformasi. Sebagian studi seperti studi C. von Luebke (2009) hanya melihat dimensi insentif politik yang menjadi pendorong bagi pemimpin daerah untuk melakukan reformasi. Lebih dari sekadar insentif politik (pemimpin reformis memperoleh legitimitasi, popularitas dan elektabilitas yang kuat) dalam perspektif rational choices, reformasi juga menjadi instrumen baru bagi penguasa untuk mengawetkan dan mendominasi kekuasaan. Ketika dominasi kekuasaan tercapai maka nilai, semangat dan hasil reformasi akan mengalami kemerosotan, bahkan menghasilkan korupsi yang endemik. Dominasi kekuasaan hingga korupsi itu merupakan dilema serius reformasi yang kurang diperhatikan studi reformasi. Ketiga, berbagai studi reformasi terjebak pada pujian dan memberikan predikat cerita sukses pada reformasi, termasuk di Jembrana. Posisi ini sangat masuk akal, mengingat reformasi adalah proses dan hasil politik yang sulit dan langka di tengah lembamnya birokrasi dan pemerintahan lokal di Indonesia. Para pengikut studi reformasi pasti sangat kecewa dan akan melakukan studi ulang ketika reformasi Jembrana membuahkan cerita sukses secara temporer tetapi ternyata membuahkan krisis dan kegagalan. Salah satu pelajaran penting bahwa cerita sukses reformasi yang temporer tidak cukup memadai untuk menjadi teladan sempurna yang disuarakan besar-besaran secara nasional. Pertanyaan tentang “cerita sukses” harus ditinjau ulang, tidak cukup memadai menjadi pertanyaan utama, dan sebaiknya memunculkan pertanyaan baru, mengapa 6 reformasi Jembrana pada tahun-tahun awal mengalami kesuksesan tetapi belakangan mengalami kegagalan. Tiga kritik penulis itu relevan untuk memahami praksis reformasi pemerintahan dan birokrasi di Indonesia yang sulit dan gagal. Reformasi tidak cukup ditempuh dengan regulasi yang progresif, kepemimpinan yang visioner, pengambangan kapasitas birokrasi, maupun inovasi organisasi dan pelayanan secara parsial. Reformasi adalah pergulatan kekuasaan yang penuh dengan pertarungan antara aktor-aktor yang mendukung versus aktor-aktor yang menolak reformasi. Pemimpin yang reformis dan visioner harus menggalang para pendukung reformasi untuk mengalahkan para penentang reformasi, serta menggunakan kekuasaannya untuk menelorkan kebijakan baru dengan berani dan nekat (audacious reform). Namun jika kemenangan reformasi yang dihasilkan oleh pemimpin visioner, legitimate, berani dan nekat itu digunakannya sebagai alat untuk mendominasi kekuasaan, maka kejayaan reformasi hanya berlangsung sementara dan bakal berujung pada kegagalan. Bagaimanapun dominasi kekuasaan selalu melemahkan kontrol publik dan menghadirkan korupsi. Di sisi lain Jembrana juga tidak cukup dilihat dengan cara pandang kekuasaan elite. Berbagai studi yang terpusat pada kekuasaan elite pada umumnya menampilkan kabar-kabar buruk, seraya tidak percaya terhadap teori arus utama (desentralisasi menumbuhkan demokrasi lokal). Para penganut studi elite yakin bahwa desentralisasi merupakan bentuk lokalisasi kekuasaan yang menyediakan ruang bagi elite lokal untuk membangun kekuasaan secara tidak demokratis (otokratis atau oligarkhis). Konsep elite capture selalu dipakai oleh studi elite untuk menunjukkan serangkaian ancaman serius bagi desentralisasi (Remy Prud’homme, 1995, P. Bardhan dan D. Mookherjee, 2000; Jean-Paul Faguet, 2004). Menurut cara pandang ini, tujuan-tujuan desentralisasi dipastikan terancam gagal ketika diserobot oleh barisan elite yang kuat, sebab tindakan itu memotong jalur delivery 7 kebijakan redistributif dan menutup akses ekonomi-politik masyarakat terutama kaum miskin dan kelompok-kelompok marginal. Serupa dengan konsep elite capture, elite predator merupakan konsep kunci yang dikemukakan Vedi Hadiz (2010). Menurut Hadiz, kemunculan politik lokal di Indonesia merupakan instrumen atau menjadi bagian dari kemunculan dan konsolidasi atas jaringan-jaringan patronase predatori yang terdesentralisasi ke daerah setelah keruntuhan Soeharto. Elite lokal bercorak predator itu memiliki kepentingan, institusi dan kendaraan untuk meraih atau mengamankan posisinya dalam tatakelola pemerintahan baru yang desentralistis-demokratis. Lokalisasi kekuasaan melalui desentralisasi meneguhkan praktik-praktik korupsi oleh elite predator, sekaligus memfasilitasi elite lokal belajar mendominasi demokrasi lokal melalui penggunaan politik uang dan berbagai instrumen untuk intimidasi dan mobilisasi politik. Dengan cara pandang kekuasaan elite itu, baik HS Nordholt (2007) dan Vedi Hadiz (2010), yang menolak narasi reformasi Jembrana, sekaligus mengatakan bahwa Bupati IGW bukan sebagai teknokrat unggul melainkan orang kuat lokal baru yang memenangkan kekuasaan dengan cara membagi-bagi uang kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Karya-karya di atas memang sangat provokatif dan meyakinkan. Secara empirik kabar-kabar buruk (oligarki, defisit politik, lokalisme, korupsi, konflik dan sebagainya) ditemukan secara menyolok di sebagian besar daerah di Indonesia. Tetapi karya-karya itu mengandung beberapa kelemahan. Pertama, konsepkonsep kunci (boss lokal, raja kecil, orang kuat, mafia lokal, negara bayangan, elite predator, dan sejenisnya) telah menjadi jargon parsimoni yang simpel dan telah mengalami inflasi dan involusi. Seperti halnya kacamata kuda, studi-studi elite itu akan menggunakan konsep kunci itu untuk menghakimi setiap daerah, tanpa melihat konteks lokal yang unik dan beragam. Para pengikut studi elite selalu setia pada jargon-jargonnya setiap kali mendatangi dan meneliti daerah-daerah yang berbeda. Dengan kalimat lain, mereka dengan mudah menjatuhkan predikat 8 “orang kuat” (atau jargon-jargon lain) kepada penguasa daerah yang mereka kaji. Kalau mereka sudah mengatakan “orang kuat” di setiap daerah, lalu what next? Kedua, tanpa mengembangkan inovasi cara pandang dan analisis yang mendalam, studi-studi elite selalu menunjukkan cara-cara lama yang digunakan elite lokal dalam membangun dan mengawetkan kekuasaan. Cara-cara lama itu seperti penggunaan jaringan patronase, politik parokhial, politik uang, kekerasan dan lain-lain. Narasi seperti ini, bagi penulis, tidak terlalu relevan untuk memahami kisah Jembrana, meskipun IGW juga menggunakan cara-cara lama dalam membangun kekuasaan. Tetapi studi elite studi elite tidak memperhatikan bahwa IGW juga menggunakan kecerdasan dan reformasi untuk membangun dan mengawetkan kekuasaan. Melalui reformasi, Bupati IGW mampu secara efektif mendongkrak kepercayaan dan dukungan mayoritas rakyat Jembrana, sekaligus melemahkan lawan-lawan politiknya. Karena itu studi elite yang terpusat pada pergulatan kekuasaan tidak mampu menangkap dan menjelaskan drama reformasi Jembrana secara utuh dan kontekstual. Bagi penulis, kabar baik Jembrana yang dikaji oleh studi reformasi dan kabar buruk yang dipotret oleh studi elite tidak cukup memadai. Pertarungan antara reformasi dan kekuasaan maupun antara kabar baik dan kabar buruk di Jembrana sungguh menghadirkan conundrum (teka-teki yang pelik dan rumit) yang menarik dan menantang, yang sekaligus menjadi titik pijak studi ini. Untuk memperoleh pengetahuan yang utuh tentang kejayaan dan keruntuhan kekuasaan dan reformasi di Jembrana tentu dibutuhkan kajian yang induktif dan kontekstual. Dengan cara yang induktif dan kontekstual, studi ini handak memecahkan conundrum Jembrana, dengan mengangkat tema utama “politik di balik reformasi” (the politics behind the reform), yakni politik di balik kejayaan dan keruntuhan reformasi maupun kekuasaan Bupati IGW. Politik di balik reformasi mengandung makna bahwa di balik reformasi ada kekuasaan dan dibalik kekuasaan ada reformasi, yang hadir dalam bentuk pergulatan Bupati IGW dalam membangun 9 kekuasaan dan melancarkan reformasi, yang mengalami kejayaan ganda tetapi berakhir dengan keruntuhan. B. Pertanyaan Penelitian Studi ini berangkat dari sebuah pertanyaan besar: bagaimana kekuasaan bekerja di balik reformasi? Bagaimana pergulatan kekuasaan dalam proses reformasi? Bagaimana cerita sukses reformasi diraih dengan pergulatan kekuasaan? Bagaimana kontestasi reformasi bekerja di balik pergulatan kekuasaan? Bagaimana reformasi digunakan sebagai instrumen konsolidasi dan dominasi kekuasaan? Untuk menjawab pertanyaan besar itu, studi ini hendak melakukan pelacakan pada tiga sisi secara kontekstual di Jembrana. Pertama, pelacakan dari sisi aktor. Bagaimana Bupati IGW membangun kekuasaan dengan reformasi? Bagaimana Bupati IGW menggunakan kekuasaan untuk melancarkan reformasi? Bagaimana perjalanan IGW dalam meraih kejayaan sampai dengan menuai keruntuhan di ujung kekuasaannya? Siapa kekuatan yang mendukung dan melawan IGW? Kedua, pelacakan dari sisi pertarungan politik. Bagaimana IGW menggalang pendukung dan mengalahkan penentangnya untuk meraih kejayaan? Bagaimana pertarungan dalam perjuangan reformasi dan kekuasaan? Bagaimana pertarungan antara kekuasaan dan reformasi? Bagaimana pergulatan kekuasaan membuahkan reformasi, bagaimana reformasi menghasilkan kekuasaan, dan bagaimana kekuasaan meruntuhkan reformasi? Bagaimana para penentang melawan reformasi dan kekuasaan yang berujung pada keruntuhan Bupati IGW? Ketiga, pelacakan dari sisi konteks. Mengapa kekuasaan IGW dan reformasi sempat membuahkan kejayaan pada tahun-tahun awal? Mengapa kejayaan IGW yang dibangun dengan konsolidasi kekuasaan dan reformasi akhirnya mengalami keruntuhan? Mengapa reformasi mengalami keruntuhan bersamaan dengan keruntuhan sang bupati? Apa konteks dan bagaimana konteks itu membentuk pertarungan politik serta kejayaan dan keruntuhan Bupati IGW? 10 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Studi ini bertujuan mengkaji ulang teori reformasi dan teori kekuasaan elite, sekaligus membangun teori alternatif tentang “kekuasaan dalam reformasi”, baik kekuasaan sebagai alat reformasi dan reformasi sebagai alat kekuasaan. Untuk mencapai tujuan besar-makro ini, penulis melakukan eksplorasi, pemahaman dan penjelasan terhadap kesuksesan dan krisis reformasi di Jembrana, yang berjalan bersama dengan kejayaan dan keruntuhan Bupati IGW. Berbasis pada tujuan itu, studi ini berharap memberikan sejumlah manfaat akademik dan praksis. Secara akademik studi ini tidak hanya memperkaya analisis politik kontekstual, tetapi juga menyajikan cara pandang dan model baru yang lebih kritis dalam melihat reformasi dan kekuasaan. Penulis berharap bahwa hasil studi ini bermanfaat sebagai referensi bagi sarjana ilmu politik dan administrasi publik agar tidak mudah latah bertutur tentang cerita sukses reformasi, atau terjebak pada citra reformis pada sang pemimpin, sekaligus juga tidak gampang latah menuding orang kuat atau elite predator. Kisah cerita sukses reformasi maupun pemimpin reformis pada satu kutub dan kisah orang kuat pada kutub lain memang merupakan fenomena politik nyata. Tetapi analisis politik menjadi dangkal kalau penilaian dilakukan secara cepat dan latah. Studi ini menyajikan pelajaran dan cara pandang baru dengan memperhatikan konteks dan dinamika pergulatan kekuasaan dalam reformasi, sehingga bisa melihat dengan baik mengapa sukses reformasi bisa dibangun, tetapi mengapa berakhir dengan kegagalan; serta mengapa dan bagaimana orang kuat lahir karena reformasi dan mengapa orang kuat bisa runtuh. Secara praksis studi ini tidak secara eksplisit memberikan rekomendasi untuk para praktisi profesional. Tetapi studi ini berguna mengingatkan agar mereka tidak terpesona pada pemimpin yang berwatak malaikat, tidak berpandangan bahwa politik (kekuasaan) merupakan penghambat reformasi, serta agar mereka tidak mudah terjebak pada mantra “cerita sukses” dan “praktik baik” yang bersifat sementara dan semu. Bagaimanapun baik praktisi maupun para 11 pembelajar sering mudah kecewa ketika cerita sukses dan praktik baik itu mengalami erosi menjadi cerita gagal dan praktik buruk. Karena itu, meskipun tidak eksplisit, hasil studi ini menyajikan manfaat bagi para praktisi, khususnya tentang model reformasi yang utuh, kokoh dan berkelanjutan. D. Pencarian Kerangka Konseptual Untuk menjawab rangkaian pertanyaan penelitian, penulis berupaya melakukan pencarian dan permusan kerangka konseptual yang memadai dan relevan. Penulis hendak menempuh peta jalan (road map) sebagai berikut. Pertama, menelusuri dan mengkaji ulang terhadap beragam studi sebelumnya yang relevan dengan pertanyaan penelitian dan relevan dengan tema “kekuasaan dalam reformasi”. Seperti akan penulis tunjukkan kemudian, sejumlah studi yang tersedia tidak cukup memadai untuk memahami dan menjelaskan “kekuasaan dalam reformasi”, khususnya dalam konteks Jembrana. Kedua, penulis meminjam teori contentious politics dan teori strukturasi (agensi-struktur) untuk memahami dan menjelaskan kekuasaan dalam reformasi. Teori contentious politics antara lain mengedepankan konsep “mekanisme” – yang berbeda dengan institusi dalam dunia politik konvensional – sebagai bingkai interaksi berbagai elemen dalam contentious politics: aksi kolektif, politik dan pertarungan. Namun teori contentious politics tidak sepenuhnya relevan untuk konteks reformasi Jembrana. Penulis meminjam juga teori agen-struktur untuk memodifikasi elemen dan mekanisme contentious politics, sehingga menghasilkan sebuah bangunan mekanisme contentious reform yang dibentuk oleh tiga elemen: agensi politik (political agency), konteks politik (political context) dan pertarungan politik (political contention). Karena itu, di satu sisi kedua teori ini merupakan perspektif alternatif atas sejumlah studi yang kurang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Di sisi lain modifikasi kedua teori itu yang penulis gunakan sebagai pengantar dan kerangka untuk membangun teori contentious reform. 12 D.1. Tinjauan Pustaka Melalui tinjauan pustaka, penulis hendak melacak sejumlah literatur atau studi sebelumnya, yang relevan dengan apa dan bagaimana kekuasaan dalam reformasi. Pada bagian pertama penulis menelusuri posisi argumen beragam studi yang kemudian menjadi referensi bagi penulis untuk menunjukkan bahwa “kekuasaan dalam reformasi” mengandung dua frasa yang berkaitan, yakni “kekuasaan untuk reformasi” dan “reformasi untuk kekuasaan”. Pada bagian kedua penulis menelusuri dan menyampaikan kritik terhadap beragam literatur tentang bagaimana “kekuasaan dalam reformasi” bekerja. Dari kritik, penulis bisa membangun argumen teoretik alternatif. D.1.1. Makna “Kekuasaan Dalam Reformasi” Sebagai titik pijak, studi ini berargumen bahwa reformasi (pemerintahan, birokrasi, administrasi) bukan perkara administratif-manajerial yang apolitik sebagaimana dikonstruksi oleh para sarjana administrasi publik. Reformasi adalah politik, reformasi adalah pergulatan kekuasaan. Kecuali studi administrasi publik lama tentang reformasi, sebenarnya telah hadir banyak studi yang memperhatikan dimensi kekuasaan (politik) dalam reformasi. Namun sebagian studi mengedepankan konstruksi teoretis tentang “kekuasaan untuk reformasi”, yang menempatkan kekuasaan sebagai variabel bebas atas reformasi, insentif politik dalam reformasi, maupun kotestasi politik dalam proses reformasi. Penulis sempat tertarik pada tema Journal of Communist Studies and Transition Politics (Volume 24 Nomor 1 2008) yang mengusung tema Putting Administrative Reform in a Broader Context of Power. Dengan membaca jurnal itu penulis berharap memperoleh perspektif dan pengetahuan yang memadai tentang “reformasi untuk kekuasaan”, selain tema “kekuasaan untuk reformasi”. Tetapi sejumlah artikel dalam jurnal ini tidak mengelaborasi kaitan timbal balik antara kekuasaan dan reformasi. Bahkan artikel Valeri Ledyaev, “Domination, Power and Authority in Russia: Basic Characteristics and Forms” 13 lebih banyak berbicara struktur dominasi kekuasaan yang membatasi reformasi. Sedangkan artikel Karine Clément, “New Social Movements in Russia: A Challenge to the Dominant Model of Power Relationships?”, menunjukkan masyarakat sipil sebagai aktor baru yang menantang kekuasaan dan mendorong reformasi. Masyarakat sipil mulai tumbuh, tetapi mereka menghadapi kesulitan untuk memperluas gerakan mereka dan mengafirmasi nilai, identitas dan klaim mereka di hadapan negara. Karena itu reformasi administrasi di Russia hanya melalui rekayasa teknokratis yang bekerja dalam konteks office politics negara dan birokrasi. Pada titik yang lain studi tentang kekuasaan elite cenderung abai terhadap dimensi reformasi. Studi tentang elite memusatkan perhatian pada asal-usul elite, cara elite merebut kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan, pembentukan elite predator atau orang kuat, serta pembajakan demokrasi yang dilakukan oleh orang kuat itu. Mereka lebih banyak menunjukkan cara elite dengan koersi, manipulasi, bujuk rayu, kooptasi dan suap untuk membangun dan mengawetkan kekuasaan, atau membangun dinasti politik yang berkelanjutan. Hampir tidak ada studi tentang elite yang menunjukkan kehadiran orang kuat melalui jalan reformasi atau mengangkat tema “reformasi untuk kekuasaan”. Teori elite tentu memberikan pelajaran tentang bagaimana elite membangun kekuasaan dan bagaimana terjadi dominasi segelintir elite (oligarkhi) terhadap mayoritas. Cara pandang seperti ini mengajarkan kepada penulis untuk membaca secara kritis terhadap demokrasi secara umum dan bahkan reformasi yang terjadi di Jembrana. Dengan kalimat lain, teori elite mengingatkan kepada setiap orang untuk tidak terlalu dini (prematur) memberi predikat “cerita sukses” pada reformasi Jembrana. Tetapi kalau cara pandang teori elite klasik dipakai terus-menerus (misalnya menghakimi elite capture, oligarkhi atau elite preadator sebagaimana dilakukan oleh studi elite), maka akan menghasilkan involusi yang tidak inovatif. Dinamika dan konteks lokal yang beragam tentu akan menghasilkan cara pandang yang lebih inovatif, misalnya reformasi di Jembrana tidak mungkin 14 bisa diabaikan begitu saja, setidaknya reformasi menjadi cara baru penguasa lokal seperti IGW untuk membangun kekuasaan. Melampaui teori elite itu, penulis menemukan sedikit literatur yang melihat reformasi dari sisi kekuasaan, yang berguna untuk memahami tema “reformasi untuk kekuasaan”. Tema “reformasi untuk kekuasaan” menempatkan reformsi sebagai variabel dependen yang berpengaruh terhadap kekuasaan, yakni reformasi bukan sekadar alat untuk memperkuat legitimasi, bukan juga sebagai alat untuk merombak struktur kekuasaan yang nondemokratis, melainkan reformasi sebagai alat untuk memperkuat dan mengawetkan dominasi kekuasaan. Studi Willem Van Vuuren (1985) tentang reformasi nasional di Afrika pada dekade 1980-an, misalnya, memberikan pelajaran penting tentang cara pandang reformasi sebagai alat kekuasaan. Vuuren berpendapat bahwa reformasi nasional di Afrika Selatan sebelum demokratisasi bukan sekadar merupakan manifestasi dari perubahan konstitusional dan refleksi dari pergeseran ideologi, tetapi reformasi dilakukan oleh elite untuk merawat dominasi kekuasaan. D. Acemoglu dan J. Robinson (2008) mempunyai pendapat serupa. Dengan mendasarkan diri pada teori elite klasik Gaetano Mosca, Acemoglu dan Robinson berpendapat bahwa perubahan institusi politik melalui reformasi menciptakan distribusi kekuasaan secara de jure tetapi juga menciptakan insentif bagi investasi kekuasaan secara de facto, yang secara parsial atau penuh, mampu melemahkan struktur kekuasaan de jure. Model ini, menurut mereka, sebagai bentuk pemeliharaan oligarkhi elite dan penyerobotan demokrasi. B. Arts dan JV Tatenhove (2004) memberikan argumen tentang relasi timbal balik antara kekuasaan dan reformasi (perubahan) secara menarik. Di satu sisi agen politik menggunakan tiga lapis kekuasaan (relasional, disposisional dan struktural) untuk menghasilkan reformasi (inovasi kebijakan, susunan kebijakan dan modernisasi politik). Agen memanfaatkan kapasitas kekuasaan (power capacity atau power to) dan perjuangan politik (kekuasaan transitif) untuk meraih perubahan kebijakan dengan cara melawan kehendak aktor-aktor lain yang 15 berposisi penentang dalam pertarungan zero sum game. Sebaliknya, tiga dimensi reformasi (inovasi kebijakan, susunan kebijakan dan modernisasi politik) juga menjadi jalan baru bagi pembentuk tatanan (order) dominasi dan legitimasi struktur kekuasaan. Pola ini membentuk susunan korporatis yang stabil, dimana negara menjamin perwakilan kepentingan masyarakat dan kelompok-kelompok kepentingan dalam proses politik dan kebijakan, seraya memberikan informasi, pengaruh, dan status; sementara masyarakat maupun kelompok-kelompok kepentingan memperoleh akses serta memberikan dukungan, kerjasama, disiplin dan legitimasi. Secara empirik arus reformasi di China memberikan gambaran konkret tentang pertautan antara reformasi dan dominasi. Banyak studi telah memperlihatkan dinamika, cerita sukses dan dilema reformasi China (Joseph Fewsmith, 1994; Cheng Li, 1997; Wang Gungwu dan Zheng Yongnian, 2001; Zheng Yongnian, 2004). Reformasi telah mengubah ekonomi sosialis menuju ekonomi kapitalis yang membuat China menjadi raksasa ekonomi baru, dengan percepatan dan pertumbuhan ekonomi yang fantastis. Secara sosial reformasi, yang sangat dipengaruhi oleh tradisi konfunianis, semakin memperkuat kohesi sosial dan identitas kolektif China di tengah pentas global. Namun secara politik reformasi tidak menciptakan distribusi kekusaan secara demokratis-pluralis melainkan meneguhkan dominasi kekuasaan secara otokratis-korporatis, yakni dominasi pemerintah pusat atas daerah, dominasi negara terhadap masyarakat, maupun dominasi partai politik terhadap birokrasi. Rangkaian argumen di atas memberikan keyakinan pada penulis untuk memaknai frasa “kekuasaan dalam reformasi”, yang mengandung dimensi “kekuasaan untuk reformasi” dan “reformasi untuk kekuasaan”. Tema “kekuasaan untuk reformasi” tentu sudah lazim, sejalan dengan argumen bahwa reformasi adalah pergulatan kekuasaan. Sejumlah argumen dalam tema “reformasi untuk kekuasaan” sungguh menarik dan menghilhami penulis, sebab tema itu sangat relevan dengan konteks Jembrana. Bupati IGW, selain menggunakan kekuasaan 16 untuk melancarkan reformasi, juga menggunakan reformasi untuk kekuasaan. Namun studi ini bukan meletakkan “kekuasaan dalam reformasi” dalam kerangka kekuasaan, melainkan dalam kerangka reformasi. D.1.2. Studi tentang Kekuasaan Dalam Reformasi Studi tentang kekuasaan dalam reformasi sudah banyak bertebaran, meskipun studi yang mengambil tema “reformasi untuk kekuasaan” masih sedikit. Melalui tabel 1.1 penulis memetakan sejumlah perspektif dan studi yang telah mengkaji reformasi. Penulis akan menguraikannya sekaligus menyampaikan kritik terhadap semua perspektif, kecuali perspektif teori elite dan studi reformasi untuk kekuasaan, sebab keduanya sudah penulis tampilkan sebelumnya. Namun izinkan penulis melakukan pengelompokan semua perspektif menjadi tiga kluster berdasarkan aktor penggerak reformasi: reformasi yang digerakkan oleh lembaga donor (donor driven reform) yang mengusung persepktif global governance; reformasi yang digerakkan oleh masyarakat (society driven reform) yang mencakup perspektif gerakan sosial, asosiasionalisme demokrasi lokal, maupun politik representasi merebut negera; serta reformasi yang digerakkan oleh pemimpin atau elite (elite driven reform). Tabel 1.1 Peta studi kekuasaan dalam reformasi Perspektif Global governance & neoliberal Argumen/orientasi Politik menghambat reformasi, sehingga perlu intervensi apolitik dari eksternal. Menciptakan pelayanan publik yang akuntabelresponsif, demokrasi liberal, ekonomi pasar dan kapitalisme global Aktor dan proses Lembaga internasional pemberi utang dan bantuan melakukan intervensi reformasi pemerintahan dan pembangunan ke Dunia Ketiga, dengan membawa new public management dan good governance. Konsensus global, kerjasama donor dengan pemerintah, konsultan ahli dan NGOs, melakukan diseminasi dan publikasi 17 Studi J. Tendler (1997), R. Bennett (1990), S. Burki (1999), T. Campbell (2003), World Bank (1997, 2005a, 2005b, 2007, 2008), Stone & Wright (2007), Cheung, (2005), Schoburgh, (2007), Pollitt (2001), Mosse (2005), Batley (2004), Crook dan Sverisson (2002), Manor (2004); Goetz Gerakan sosial Melawan negara, meruntuhkan otoritarianisme, demokrasi dan HAM, melawan korupsi, perjuangan keadilan gender, reformasi agraria Politik representasi dan merebut negara Negara dikuasi oleh oligarkhi elite, sementara gerakan sosial sangat lambat, sehingga negara dan kekuasaan harus direbut oleh aktor masyarakat. Asosiasionalisme demokrasi lokal Memupuk modal sosial, memperkuat masyarakat sipil, partisipasi warga, memperdalam demokrasi lokal, dan membuat pemerintah lokal semakin akuntabel Institusionalisme aktor rasional (elite led reform) Kalkulasi manfaat lebih besar daripada ongkos, atau karena insentif politik, pemimpin melakukan reformasi Institusionalisme sosiologishistoris (institutionalized reform) Reformasi sarat dengan kontestasi dan pertarungan politik antaraktor, sehingga perlu konsensus dan pelembagaan, agar ide-wacana, rekayasa kebijakan dan kelembagaan, capacity bulding, aksi kolektif, pemberdayaan. Aktor-aktor nonnegara menggelar gerakan sosial berbasis massa untuk melawan negara, protes terhadap kebijakan yang bermasalah dan diskriminatif, dan memperjuangkan kebijakan baru. Menggeser gerakan sosial ke gerakan politik Aktor-aktor pembawa reformasi menggalang dukungan, bergabung dalam partai politik, berkompetisi dalam proses elektoral untuk merebut kekuasaan Sekarang di Indonesia tengah ada trend baru,bahwa para aktivis merebut posisi kepala daerah maupun parlemen, Warga membangun organisasi masyarakat sipil, membangun kerjasama dan jaringan, mengisi ruang publik, dan civic engagement dalam pemerintahan lokal, untuk memperjuangkan kepentingan warga dan menantangkan akuntabilitas-responsivitas pemerintah lokal. Pemimpin secara visioner, berani dan nekat melakukan perubahan terhadap kebijakan, organisasi, personel, penganggaran, pelayanan publik yang pro rakyat Reformasi bisa muncul dari bawah (masyarakat), dari samping (politisi) dan bisa dari atas (pemimpin). Reformasi menjadi menjadi arena kontestasi 18 & Jenkins (2004) Clément (2008), Tarrow (1994, 1998, 2011) Hampir tidak ada studi tentan tema ini. DEMOS Indonesia (2007) hanya merekomendasikan para aktivis prodemokrasi masuk ke ranah politik merebut kekuasaan. Mietzner (2013) telah meneliti tindakan dan pengaruh politisiaktivis di DPR. Putnam (1993), Abers (2001), Heller (2001), Gaventa (2001, 2006), Avritzer (2002), Fung dan Wright (2003), Alagappa (2004), Diamond (2003), Cornwall dan Coelho (2007), Baiocchi et. al (2008), Takhesi (2006) Schneider dan Teske (1995), Grindle (2000), Pollitt and Boukaert (2004), Heyse et. al. (2006), Luebke (2009). Grindle (2004, 2007), Blom-Hansen et. al (2012), Berg & Rao, (2005), Manor (2007), Robinson (2007); Wollmann reformasi berjalan secara smart, kokoh dan berkelanjutan Teori kekuasaan elite Elite yang kuat, dominan, otokratis Reformasi untuk kekuasaan Elite reformis dominan beragam aktor, sehingga ditempuh dengan deliberasi dan konsensus kolektif. Elite melakukan bujuk rayu, suap, koersi dan manipulasi untuk meraih dan mengawetkan kekuasaan. Elite melakukan perampasan terhadap sumberdaya. Elite pradator memanfaatkan dan membajak demokrasi. Elite menggalang dukungan kekuasaan dan reformasi, menggunakan reformasi untuk melemahkan lawanlawan politik, meningkatkan legitimasi, dan meraih dominasi kekuasaan. (2008); Gains, Greasley, Peter John dan Stoker (2009) Nordholt (2007), Hadiz (2010), Sidel (2005). Vuuren (1985), Acemoglu & Robinson (2008), B. Arts dan JV Tatenhove (2005), Fewsmith (1994); Cheng Li (1997); Gungwu dan Yongnian, (2001); Yongnian (2009) Reformasi yang digerakkan dari luar oleh lembaga donor internasional (donor driven reform). Sejumlah lembaga donor seperti World Bank, UNDP, USAID, UKAid, dan lain-lain membawa perspektif “global governance” atau “agenda kebijakan baru” untuk mendesakkan reformasi pemerintahan di seluruh negara di dunia. Perspektif normatif-preskriptif ini sangat dominan, yang tersedia di banyak dokumen resmi lembaga-lembaga donor internasional maupun lietaratur yang bertitel “public sector reform” atau “public management reform”. Lembaga-lembaga internasional (pemberi utang dan bantuan) merupakan aktor penting dalam reformasi sektor publik ketika pemerintah (nasional dan lokal) di negara-negara berkembang tidak memiliki kapasitas pengetahuan dan finansial yang memadai. Mereka hadir ke banyak negara, dengan membawa bantuan dan utang, menjalin kerjasama resmi dengan pemerintah untuk melancarkan reformasi sektor publik. Di dalam negeri seperti Indonesia, lembaga-lembaga internasional bekerjasama dengan konsultan ahli, para birokrat profesional, maupun NGOs – 19 yang oleh NH Nordholt (2007) disebut sebagai kaum optimis profesional – menggelar ide, wacana dan praksis reformasi. Ide (substansi) reformasi dibimbing oleh tradisi neoliberal yang mengutamakan New Public Management (privatisasi, desentralisasi, contracting out, pemberdayaan, pemerintahan wirausaha, dan sebagainya) dan good governance (transparansi, akuntabilitas, responsivitas, kemitraan). Ide dan wacana normatif itu merupakan preskripsi reformasi (Anthony B. L. Cheung, 2005), yang dijalankan dengan praksis “program reformasi” (Eris Schoburgh, 2007). Imposisi New Public Management (NPM) dari luar itu belangsung secara apolitik dengan diskusi, keputusan, tindakan dan hasil (Pollitt, 2001). NPM dan good governance sebagai resep (preskripsi) reformasi tentu tidak relevan untuk alat deskripsi dan ekplanasi terhadap kekuaaan di balik reformasi. Namun preskripsi itu juga dijalankan secara praksis melalui pelembagaan reformasi yang digerakkan oleh pemimpin dari atas, partisipasi warga, maupun kemitraan pemerintah dengan NGOs. Lembaga donor seperti World Bank sangat optimis bahwa proyek desentralisasi, NPM, good governance, hingga community driven development menuai keberhasilan karena setidaknya telah diadopsi dan dijalankan oleh banyak negara. Paling tidak ada empat faktor yang membuat sukses tekanan internasional terhadap reformasi. Pertama, krisis menciptakan ketidakpastian, yang membuka ruang dan menciptakan insentif untuk perubahan; dan semakin banyak bentuk kritis, ada ruang yang lebih besar untuk belajar. Kedua, hadirnya pemimpin baru. Bulan madu pemimpin baru dalam transisi umumnya membuka penerimaan terhadap pembelajaran untuk perubahan. Ketiga, transisi demokrasi. Pemerintahan yang demokratis jauh lebih terbuka dengan perubahan dan beragam aktor, dibandingkan dengan pemerintan otokratis. Keempat, kapasitas negara terbatas dalam merespons beragam masalah dan tantangan, sehingga negara membuka diri untuk kerjasama, belajar dan berubah (Bermeo, 1992; Hall, 1993; McCoy, 2000; Hochstetler, 2002; Bräutigam dan Segarra, 2008). 20 Tetapi di balik optimisme program reformasi dari lembaga donor itu ada sederet kritik yang disampaikan oleh banyak sarjana. Pertama, perubahan hanya semu dan sementara yang gagal menghasilkan perubahan berkelanjutan, sekaligus tidak ada hubungan dekat antara apa yang negara lakukan dengan apa yang mereka janjikan ketika mereka menandatangani utang atau bantuan (Killick 1998; Burnside dan Dollar 2000; Drazen 2002). Kedua, ada kepentingan politik di negara-negara berkembang yang sering resisten meskipun lembaga-lembaga internasional bekerjasama dengan NGOs nasional telah melakukan tekanan perubahan (Nelson, 1995; Fox, 2000; Hunter dan Brown, 2000; Goldman, 2005). Pemerintah sering mempertanyakan legitimasi NGOs dan menuding NGOs sebagai “agen asing”. Ketiga, keterlibatan aktor-aktor internasional dalam reformasi kebijakan cenderung bersifat pemaksaaan (imposition) yang mengurangi kepekaan politik lokal atas proses reformasi (Eris Schoburgh, 2007), melemahkan kepemilikan lokal atas reformasi (David Mosse, 2005), dan sekaligus merusak hubungan akuntabilitas antara warga, pembuat keputusan dan penyedia layanan publik (Richard Batley, 2004). Memang NPM dan good governance sebagai resep reformasi sektor publik tersebar ke penjuru dunia, termasuk Indonesia, baik level nasional maupun daerah. Mulai dari privatisasi, kemitraan publik dan privat dalam pengadaan barang dan jasa, penggunaan tenaga alih daya (outsourcing), sampai dengan pelayanan satu atap (one stop service) merupakan pengaruh perspektif global governance. Di Jembrana juga terdapat alih daya dan pelayanan satu atap. Tetapi Bupati IGW sama sekali tidak bekerjasama dengan lembaga internasional, juga tidak menggelar ide dan wacana demokrasi maupun good governance, dalam menggelar pertarungan kekuasaan dan reformasi di Jembrana. Karena itu studi ini mengabaikan reformasi yang digerakkan oleh lembaga-lembaga internasional yang membawa persepktif global governance. 21 donor Reformasi yang digerakkan masyarakat. K. Weyland (2008) maupun C. von Luebke (2009) menyebutnya sebagai demand side based reform atau reformasi yang berasal dari sisi tuntutan/desakan masyarakat dari bawah. Gerakan sosial merupakan bentuk reformasi yang digerakkan oleh masyarakat dengan cara radikal. Gerakan sosial juga sering disebut sebagai aksi kolektif. Sydney Tarrow (1994) misalnya, mendefinisikan aksi kolektif sebagai perlawanan bersama oleh rakyat (people) dengan upaya bersama dan solidaritas dalam interaksi yang berlanjut dengan elite, musuh-musuhnya dan pemegang kekuasaan. Aksi kolektif hadir dalam bentuk asosiasi kepentingan, gerakan protes sosial, pemberontakan, pembangkangan, pemogokan, kampanye antikorupsi dan lain-lain. Gerakan sosial membentang luas dari bentuk gerakan buruh, gerakan petani, gerakan HAM, gerakan persamaan warga negara, gerakan demokrasi antiotokrasi, gerakan lingkungan, gerakan multikulturalisme, gerakan antikorupsi, dan masih banyak lagi. Orientasi gerakan sosial dalam reformasi tampak beragam, seperti gerakan memperjuangkan kebebasan sipil, melawan dan meruntuhkan rezim otoritarianisme seperti gerakan reformasi 1998, gerakan melawan kebijakan yang bermasalah, menekan pemerintah dan parlemen agar melakukan reformasi, maupun gerakan melawan dan memberantas praktik korupsi penguasa. Jika gerakan sosial secara radikal melawan negara, perspektif masyarakat sipil dan asosiasionalisme demokrasi lokal hadir lebih moderat, yakni menjalin kemitraan dengan pemerintah dan keterlibatan masyarakat dalam arena pemerintahan lokal. Robert Putnam (1993), yang dipengaruhi oleh Alexis Tocqueville, merupakan ilmuwan terkemuka yang meyakini vitalitas asosionalisme masyarakat sipil untuk memperdalam demokrasi dan reformasi pemerintahan lokal. Dengan studi yang panjang di Italia, Putnam membangun argumen yang bertenaga bahwa desentralisasi menumbuhkan modal sosial dan tradisi kewargaan di aras lokal. Partisipasi demokratis warga telah membiakkan komitmen warga yang luas maupun hubungan-hubungan horizontal: kepercayaan (trust), toleransi, kerjasama, dan solidaritas yang membentuk apa yang disebut 22 Putnam sebagai komunitas sipil (civic community). Indikator-indikator civic engagement (seperti solidaritas sosial dan partisipasi massal) yang membentang luas berkorelasi tinggi dengan kinerja pembangunan ekonomi dan kualitas kehidupan demokrasi. Selama seperempat abad terakhir, desentralisasi di Italia telah mentransformasikan kultur politik elite yang demokratis. Pembentukan pemerintahan lokal yang mendapatkan sejumlah kekuasaan otonom dan kontrol atas sumberdaya lokal, menghasilkan suatu tipe politik yang secara ideologis tidak terlalu terpolarisasi, lebih moderat, toleran, pragmatis, lebih fleksibel dan suatu penerimaan mutual yang lebih besar di antara hampir semua partai. Secara berangsur-angsur warga mulai mengidentifikasi diri dengan pemerintahan lokal dan bahkan lebih menghargainya ketimbang pemerintahan nasional. Putnam juga menegaskan bahwa desentralisasi dan demokratisasi lokal mempunyai potensi besar untuk merangsang pertumbuhan organisasi-organisasi dan jaringan masyarakat sipil (civil society). Arena kehidupan komunitas dan lokal lebih menawarkan cakupan terbesar bagi organisasi-organisasi independen untuk membentuk dan mempengaruhi kebijakan. Pada level lokal, rintangan-rintangan sosial dan organisasional terhadap aksi kolektif lebih rendah dan sederet masalah yang menuntut perhatian (dari layanan sosial sampai transportasi dan lingkungan) berdampak langsung pada kualitas hidup warga. Keterlibatan langsung warga dalam penyelenggaraan layanan publik pada level lokal menghasilkan suatu peluang penting untuk memperkuat keterampilan warga secara individual dan akumulasi modal sosial, seraya membuat pelayanan publik lebih reponsif dan akuntabel. Perspektif Putnam itu sangat berpengaruh terhadap perspektif dan studi para sarjana generasi berikutnya. M. Alagappa (2004), menyampaikan sebuah kesimpulan bahwa organisasi masyarakat sipil berperan penting membuat perubahan politik yang mengarah pada institusi dan sistem politik yang lebih terbuka, partisipatoris dan akuntabel. Melimpahnya ruang baru bagi partisipasi warga menghasilkan reformasi tatapemerintahan (Cornwall dan Coelho, 2007). Di Brasil, sejumlah studi menunjukkan vitalitas masyarakat sipil menjadi kekuatan 23 pengimbang terhadap dominasi penguasa lokal. Organisasi masyarakat sipil bukan saja memperkuat suara-suara kritis, tetapi juga melakukan transformasi norma dan praktik demokrasi lokal (Avritzer 2002, Gianpaolo Baiocchi etl. al. 2008) Di Indonesia, Ito Takhesi (2006), misalnya, menunjukkan peran vital organisasi masyarakat sipil dalam reformasi pemerintahan lokal di Kabupaten Bandung. Ketika kekuasaan tidak hanya terpusat di tangan pemerintah daerah, tetapi mengalami penyebaran ke berbagai institusi politik, dan hal ini menciptakan kompetisi politik, pemerintah daerah berupaya meningkatkan akuntabilitas melalui kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil (OMS). OMS, yang memiliki pengetahuan tentang kebijakan publik dan berjaringan dengan pemerintah daerah, mampu memainkan peran penting dalam transformasi konsep tentang reformasi pemerintahan lokal ke dalam model perencanaan partisipatoris dan pemberdayaan desa secara konkret. Dalam situasi kompetisi politik, keterlibatan OMS dalam reformasi pemerintahan lokal memfasilitasi komunikasi, mengurangi ketegangan antaraktor politik, serta menjembatani kesenjangan antara negara dan masyarakat sipil. Penulis sangat sadar bahwa kehadiran organisasi masyarakat sipil itu masih prematur, rentan, dan tidak mungkin membuahkan perubahan secara cepat karena masih kuatnya struktur politik oligarkhis. Masyarakat sipil tentu bukanlah malaikat sempurna, yang tidak luput dari masalah-masalah yang serius. Organisasi masyarakat menampakkan dua sisi yang paradoks, ada yang civil tetapi juga ada yang uncivil. Di satu ada gerakan sosial yang hendak menuntut perubahan, tetapi di sisi lain ada kelompok masyarakat yang berburu money politics pada perhelatan pemilihan umum maupun pilkada. Ada juga organisasi berbasis primordial yang menebar kekerasan dan konflik horizontal. Tetapi modernisasi maupun pembangunan yang berjalan selama ini tentu menghasilkan begitu banyak ragam generasi: ada generasi yang hedonis tetapi juga ada generasi transformatif. Generasi baru yang transformatif ini adalah kekuatan masyarakat sipil, mereka adalah kalangan terdidik baik di dunia pendidikan maupun organisasi masyarakat, 24 yang mempunyai integritas moral, kritis, beradab dan berpandangan visioner. Mereka menaruh perhatian pada isu-isu publik, antikemapanan, antilokalisme, antikorupsi dan tentu juga kritis terhadap pemerintahan daerah, sehingga mereka menjadi kekuatan kontrol sosial yang memberi makna terhadap daerah. Berbeda dengan pemilihan umum yang dalam tempo singkat memperlihatkan “hasil siapa memperoleh apa”, pertumbuhan masyarakat sipil beserta hasil dan manfaatnya tidak bisa dirasakan secara langsung saat ini. Ralp Dahrendorf (1990) pernah menyampaikan petuah berharga: “Sebuah negara bisa membangun demokrasi politik selama 6 bulan, bisa menciptakan ekonomi pasar selama 6 tahun, tetapi tumbuhnya masyarakat sipil yang kuat di Eropa Timur membutuhkan waktu selama 60 tahun”. Di balik petuah itu tampak mengandung makna bahwa gerakan sosial, partisipasi warga, maupun gerakan masyarakat sipil berperan penting terhadap transformasi politik menuju demokrasi, termasuk membuat pemerintahan lokal yang lebih responsif dan akuntabel. Kehadiran kekuatan masyarakat bukan menggerakkan reformasi dalam tempo yang cepat. Studi Grindle (2007) terhadap 30 daerah di Meksiko maupun studi C. Von Luebke (2009) atas 8 kabupaten di Indonesia, menunjukkan bahwa reformasi pemerintahan lokal datang dari pemimpin daerah ketimbang dari aktor masyarakat. Kehadiran kekuatan masyarakat memang tidak serta merta menghasilkan perubahan kebijakan maupun struktur dan institusi pemerintahan lokal. Tetapi baik komunitas warga maupun masyarakat sipil tidak bisa dianggap remeh. Studi penulis bersama YAPPIKA di enam daerah (Bandar Lampung, Pekalongan, Surakarta, Malang, Kupang dan Sinjai) menemukan vitalitas komunitas warga dan LSM menantang akuntabilitas pelayanan publik. Pertama, kekuatan masyarakat menjadi pengimbang dan kontrol publik terhadap pemerintah lokal, termasuk menjadi watch dog terhadap korupsi. Kedua, mereka menciptakan ruang-ruang publik dan membangkitkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan lokal, termasuk pengaduan mereka terhadap pelayanan publik. Ketiga, unit pelayanan 25 (seperti Puskesmas, RSUD, Dinas Dukcapil hingga PLN) memberikan respons positif terhadap tuntutan masyarakat, yang membuat mereka melakukan perubahan pelayanan, baik dari sisi standar, prosedur, kualitas, biaya dan akses (Sutoro Eko, 2014). Karena kekuatan gerakan masyarakat sipil hanya mampu mendorong transformasi secara gradual dan kurang signifikan mendesakan reformasi, maka lahirlah perspektif politik representasi yang merebut negara (reclaiming the state). Penulis menyebut perspektif ini sebagai aliran ketiga dalam masyarakat sipil, dan sekaligus aliran keempat dalam politik representasi. Dari sisi masyarakat sipil, perspektif “merebut negara” (gerakan sosial) melampaui “melawan negara” dan “berkawan dengan negara” (partisipasi dan citizen engagement). Dalam perspektif “merebut negara”, masyarakat tidak lagi menantang kebijakan atau mempengaruhi kebijakan, melainkan menentukan kebijakan secara langsung. Dari sisi representasi, selama ini dikenal ada tiga bentuk. Pertama, representasi dengan rantai kedaulatan rakyat melalui hubungan antara agen dan principal. Dalam representasi politik, orang-orang yang diwaliki disebut konstituen atau principal dan yang mewakili disebut secara populer sebagai wakil rakyat atau agent. Pembentukan wakil atau agent dilakukan dengan pemilihan umum (election), dimana konstituen memberikan mandat atau perintah kepada wakil dan wakil mengambil keputusan atas nama konstituen, serta akuntabel dan responsif pada konstituen. Kedua, partisipasi rakyat secara massif dan langsung, tanpa melalui perantara atau agen. Ketiga, representasi asosiasional melalui NGOs (Olle Tornquist, 2009). Perspektif merebut negara menjadi bentuk keempat dalam politik representasi. Dalam konteks ini merebut negara mempunyai dua makna. Pertama, partisipasi radikal membangun demokrasi yang kuat (strong democracy) untuk merebut arena dan sumberdaya negara. Kisah participatory budgeting di Porto Alegre, misalnya, memberikan contoh terkemuka kemenangan radikalisme 26 masyarakat sipil dan masyarakat politik (partai politik) yang sukses melakukan reklaim atas negara (Hillary Wainwraight, 2003; dan Bruno Jobert, 2008). Kedua, representasi organisasi rakyat, organisasi masyarakat sipil, atau aktivis prodemokrasi dan reformasi merebut jabatan-jabatan publik seperti parlemen atau kepala daerah. Dalam tema merebut negara, aktor-aktor masyarakat berubah dari prinsipal ke agen. Perspektif ini sebenarnya tidak begitu populer, sebab merebut negara sama saja dengan kombinasi antara partisipasi rakyat dan asosiasionalisme yang masuk ke ranah rantai kedaulatan rakyat. Dilihat dari rantai kedaulatan rakyat, setiap orang – entah dari organisasi rakyat, NGOs, pedagang, petani, nelayan, buruh dan sebagainya – mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi agen (wakil rakyat). Tetapi orang biasa merebut negara dengan menjadi agen bukan representasi yang konvensional. Hal ini menjawab struktur kepartaian yang oligarkhis-eksklusif, representasi mengambang, elite capture dan oligarkhi elite yang tidak pro rakyat. Di Indonesia, organisasi masyarakat sipil berhasil mendesakkan representasi calon independen dalam sistem pemilihan kepala daerah, dengan tujuan agar aktor-aktor prorakyat, prodemokrasi dan proreformasi mempunyai kesempatan merebut negara melalui kontestasi sebagai calon kepala daerah, di tengah struktur partai yang oligarkhis-eksklusif. Sementara DEMOS dan Pergerakan, merupakan organisasi masyarakat sipil yang lebih jauh mengembangkan perspektif masyarakat merebut negara. Pilihan ini didasari oleh beberapa hal dan juga dipengaruhi oleh keyword ala Olle Tornquist (2006, 2009) seperti demokrat mengambang, representasi mengambang, desentralisasi oligarkhis, pembajakan demokrasi, representasi popular dan sebagainya. Pertama, elite telah membajak demokrasi, representasi bersifat mengambang dan suasana apolitik. Kedua, para aktivis prodemokrasi tidak mempunyai basis dukungan kerakyatan yang kuat, serta tidak terlibat dalam pemerintahan dan representasi. Karena tidak adanya konstituen yang jelas, para aktor prodemokrasi seakan-akan 27 menjadi “demokrat mengambang” di tengah-tengah massa mengambang. Dengan tetap memegang teguh prinsip nonpartisan, elemen-elemen masyarakat sipil prodemokrasi cenderung menggunakan cara-cara tradisional dalam memobilisasi dukungan terhadap kebijakan mereka. Ketiga, pengalaman Lech Wałęsa (tukang listik, aktivis serikat pekerja) yang berhasil menjadi presiden Polandia (19901995) maupun pengalaman Evo Morales (petani kokain dan aktivis gerakan sosialis) yang sukses menjadi Presiden Bolivia 2006, selalu menjadi referensi besar bagi perspektif masyarakat merebut negara. Karena itu DEMOS merekomendasikan dan secara praksis memfasilitasi para aktivis prodemokrasi di banyak daerah mengubah haluan dari gerakan sosial ke gerakan politik, yakni merebut jabatan publik di parlemen dan kepala daerah. Namun DEMOS tampaknya belum melakukan overview terhadap signifikansi kehadiran politisi-aktivis tersebut terhadap democratic reform. Apakah para politisi-aktivis yang menjadi kepala daerah maupun parlemen berpengaruh secara signifikan terhadap reformasi dan demokrasi? DEMOS belum memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Studi Marcus Mietzner (2013), misalnya, bisa menjadi referensi untuk menjawab signifikansi perspektif merebut negara. Dia telah melakukan studi tentang representasi aktivis ke dalam DPR pada pemilu 2009, yang berjumlah 37 orang (setara 7% dari total 560 anggota DPR), lebih besar dari 2% mantan tentara dalam DPR. Dari 37 anggota politisi-aktivis itu, Marcus membagi menjadi 3 kategori. Pertama, politisiaktivis yang berorientasi pada karir, yakni mencari kedudukan dan kekayaan ekonomi. Dengan kalimat lain, aktivis hijrah menjadi politisi DPR dalam rangka mencari kerja. Kedua, politisi-aktivis berorientasi politik, yang memupuk kekuasaan atas dirinya sendiri dan untuk partainya. Kedua kelompok ini mempunyai kesamaan. Mereka terjebak (kooptasi) dalam pragmatisme dan patronage politik, termasuk dalam pencarian dana melalui cara yang tidak transparan dan tidak akuntabel. Ketiga, kelompok politisi-aktivis yang berorientasi pada perubahan dan demokrasi. Mereka tidak terjebak dalam korupsi dan 28 patronase politik sebagaimana dilakukan oleh kelompok pertama dan kedua, namun kelompok reformis ini tidak mampu mendorong perubahan besar, kecuali hanya mendorong sebagian produk legislasi yang mengarah pada reformasi. Kekuatan ini tidak mampu mendobrak “demokrasi patronase” yang terbangun di Indonesia pasca-Soeharto. Reformasi yang digerakkan dari atas oleh elite (pemimpin). Perspektif ini yang paling dominan dalam studi reformasi atau dalam kerangka “kekuasaan untuk reformasi”. Sejumlah studi menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa elite atau kepemimpinan (kekuasaan, kapasitas, strategi, tindakan, dan lain-lain) merupakan variabel penjelas utama atas cerita sukses reformasi (Merilee Grindle, 2004 dan 2007, Rikke Berg dan Nirmala Rao, 2005, James Manor, 2007, Mark Robinson, 2007; Hellmut Wollmann, 2008; Francesca Gains, Stephen Greasley, Peter John dan Gerry Stoker, 2009). Ada dua aliran dalam studi reformasi berbasis elite ini, yakni teori aktor rasional atau yang biasa disebut teori kalkulus; dan teori pelembagaan reformasi yang dipengaruhi oleh institusionalisme sosiologis-historis. Teori kalkulus dalam reformasi antara lain melihat insentif, pembatas atau hambatan, kesempatan, serta perhitungan atas ongkos, manfaat (hasil) dan risiko. Teori kalkulus mengatakan bahwa aktor bertindak sesuai dengan nalar konsekuensi. Pendekatan ini memperhatikan secara langsung terhadap prosedur, institusi dan struktur yang melingkupi kebijakan, yang mempengaruhi kesempatan bagi aktor politik untuk mengubah kebijakan. Dalam cara pandang ini, hambatan perubahan bisa muncul ketika struktur dan institusi membatasi prakarsa reformasi, dan karena itu kesempatan aktor sangat terbatas dalam mendorong reformasi. Pemain veto sering disebut sebagai pembatas/penghambat, yang menolak usulan dari pembawa reformasi (Immergut, 1992; Cortell & Peterson, 1999; Pollitt & Bouckaert, 2004; Bannink dan Sandra Resodihardjo, 2006). Parlemen, pemerintah nasional maupun partai politik dapat disebut sebagai 29 pemain veto, yang bisa menolak usulan reformasi dari bupati. Partai politik dan parlemen bisa menghambat atau menolak usulan reformasi karena reformasi berisiko mengancam kepentingan mereka terhadap anggaran. Selain ada hambatan, tentu juga ada kesempatan. Krisis merupakan pintu kesempatan yang sangat besar bagi aktor pembawa reformasi. Krisis dapat dikonstruksi secara deliberatif oleh aktor yang mempunyai motivasi melakukan reformasi. Aktor reformis dapat menggunakan retorika krisis untuk mendiskreditkan struktur dan kebijakan sekaligus melegitimasi untuk melakukan gebrakan perubahan yang drastis. Di satu sisi, hambatan reformasi dapat dengan mudah ditembus dengan legitimasi krisis, dan di sisi lain legitimasi krisis memudahkan perubahan kebijakan (Grindle & Thomas, 1991; Cortell & Peterson, 1999; Kuipers, 2006; Bannink dan Sandra Resodihardjo, 2006). Dengan kalimat lain, pemimpin reformasi dapat memanfaatkan krisis sebagai jendela kesempatan untuk menembus hambatan dan melangkah maju melakukan reformasi. Proses menembus hambatan, memanfaatkan kesempatan, melakukan kalkulasi reformasi merupakan jantung perhatian pendekatan institusional atas reformasi. Semua ini adalah perkara kedua yang bisa dimainkan oleh elite. Perkara pertama sebenarnya terletak pada insentif dan keberanian. Menurut teori kalkulus, reformasi memang bisa terjadi kalau ada kepastian perhitungan ongkos yang besar tetapi menghasilkan manfaat dan hasil yang besar pula, dengan risiko yang kecil. Kalau aktor takut dengan biaya besar, apalagi risiko besar, maka dia tidak berani melakukan reformasi. Tetapi insentif dan keberanian mampu menembus pembatas kalkulus itu. , Faktor insentif politik itu menonjol dalam studi Christian von Luebke (2009). Luebke berangkat dari pertanyaan, mengapa banyak pemerintah daerah berkinerja baik, sementara yang lain-lainnya tampil buruk? Untuk menjawab pertanyaan itu, dia melakukan studi secara deduktif-komparatif di delapan kabupaten di Indonesia (Solok, Pesisir Selatan, Klaten, Kebumen, Karangasem, Gianyar, Bima dan Lombok Timur). Solok, Kebumen, Gianyar dan Lombok Timur 30 dikategorikan sebagai daerah yang berkinerja baik dan bersih dari korupsi, sementara Pesisir Selatan, Klaten, Karangasem dan Bima dikategorikan tampil buruk dan koruptif. Ia mengambil kesimpulan bahwa tekanan sisi tuntutan (demand-side pressures) dari pengusaha lokal, asosiasi dan DPRD tidak cukup signifikan membawa perubahan dibandingkan dengan tekanan sisi penyediaan (supply-side pressures) dari pemimpin pemerintah lokal. Dalam konteks transisi menuju desentralisasi demokratis, tekanan masyarakat sangat dibatasi oleh kelemahan aksi kolektif dan insentif politik yang busuk (jahat). Sebaliknya, pemimpin daerah, mempunyai kekuasaan kuat dan insentif baru untuk melancarkan reformasi kebijakan. Keberanian, bahkan kenekatan, juga merupakan faktor lain yang membangkitkan adrenalin pemimpin. Seorang pemimpin yang mempunyai insentif besar (berprestasi, memperoleh dukungan rakyat, mampu mempertahankan kekuasaan, atau meraih kekuasaan lebih besar) bisa nekat melakukan reformasi meskipun harus menggunakan ongkos besar dan manfaat besar, tetapi juga dengan risiko besar. Studi Grindle (2000), yang menemukan konsep reformasi nekat (audacious reform) memberikan contoh hal ini. Studi-studi itu bisa penulis katakan telah membuahkan parsimoni “tidak ada pemimpin yang kuat, tidak ada reformasi”. Tetapi studi mereka tidak cukup memahami dinamika reformasi yang sangat kompleks, dan tidak memberikan eksplanasi bagaimana dinamika pasca reformasi serta mengapa ada reformasi yang gagal. Pendekatan aktor rasional mampu memahami insentif politik yang diperoleh oleh aktor, tetapi ia kurang memahami kondisi dan proses bagaimana kepentingan dan tindakan aktor berjalan (Doug MacAdam, Sidney Tarrow dan Charles Tilly, 2004). Pendekatan kalkulus yang kurang memperhatkan proses itu dikembangkan oleh pendekatan institusionalisasi reformasi. Pendekatan ini tidak hanya melihat proses dan dinamika reformasi, tetapi juga memperhatikan keberhasilan dan kegagalan reformasi. J. Manor (2006), misalnya, mengkaji kesuksesan dan 31 kegagalan reformasi di di dua negara bagian India. Di satu sisi, reformasi bisa gagal bila: (a) reformasi mempengaruhi kepentingan vital kelompok-kelompok yang kuat; (b) pemimpin enggan dan ragu-ragu menyentuh sektor-sektor yang akan direformasi; dan (c) reformasi mengancam kerusakan serius pada partai yang berkuasa. Di sisi lain, keberhasilan reformasi tergantung pada pemimpin yang mempunyai komitmen kuat dan mempunyai taktik politik yang canggih untuk menerobos institusi, sekaligus meraih dukungan yang besar dan mengalahkan kelompok-kelompok oposisi. Tetapi kepemimpinan yang sukses itu juga tergantung pada konteks politik: (a) daya tahan, prediktabilitas dan legitimasi institusional yang dirancang oleh reformasi; (b) perubahan komposisi elite dan keragaman organisasi masyarakat sipil yang mendukung reformsi; (c) reformasi tidak merusak stabilitas fiskal; (d) dan mempunyai kapasitas teknis. Studi Merilee Grindle (2007) tentang reformasi dan kinerja pemerintahan daerah di 30 daerah di Meksiko menjadi contoh menarik dari sisi pendekatan institusionalisasi politik. Dia menelusuri mengapa satu daerah mengalami perubahan dan mempunyai kinerja baik, sementara daerah lain tidak demikian. Variabel apa yang yang secara komparatif bisa menjelaskan variasi antardaerah itu? Buku itu dengan metode deduktif komparatif mengajukan hipotesis tentang beberapa variabel yang berpengaruh terhadap perubahan dan kinerja pemda, yakni kompetisi politik dalam pemilhan lokal, kewirausahaan pemimpin, modernisasi birokrasi dan partisipasi masyarakat sipil. Setelah melakukan studi lapangan, Grindle melakukan verifikasi dan penyempurnaan atas hipotesis yang dibangun sebelumnya. Ada beberapa argumen penting Grindle sebagai kesimpulan utama buku itu. Pertama, kompetisi politik dan kinerja pemerintah lokal mempunyai hubungan yang tidak langsung. Kedua, kompetisi merupakan kondisi penting yang memfasilitasi kesempatan untuk melakukan perubahan. Ketiga, kepemimpinan merupakan variabel yang konsisten terhadap perubahan kinerja pemerintahan lokal. Komitmen, kepribadian yang baik dan jaringan yang dimiliki pemimpin lokal menjadi kekuatan penggerak 32 perubahan. Keempat, kepemimpinan wirausaha, yang didorong oleh kompetisi politik yang terbuka, merupakan variabel yang sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap perubahan, karena kelemahan struktur institusional. Kelima, modernisasi birokrasi, bukanlah variabel yang bediri sendiri, tetapi dibentuk oleh variabel pertama dan kedua, dan ia digerakkan oleh sang pemimpin. Keenam, pengembangan kapasitas, sebagai komponen utama dalam modernisasi birokrasi, merupakan sebuah alat bagi kepemimpinan yang efektif, bukan sebagai sumber independen bagi perubahan. Ketujuh, kekuatan civil society sama sekali tidak berhubungan dengan kompetisi politik, kepemimpinan dan modernisasi birokrasi; bahkan lemahnya civil society di ranah lokal tidak berpengaruh terhadap perubahan. Jika studi itu mengutamakan keterkaitan beragam variabel penjelas, studi Grindle (2004) menyajikan proses institusionalisasi reformasi pendidikan di Amerika Latin, sebagaimana tersaji dalam bagan 1.1. Bagan itu secara jelas menunjukkan bahwa reformasi mengandung proses teknokrasi sekaligus pertarungan politik (contentious politics) beragam aktor. Arena menggambarkan sebuah road map reformasi yang berhasil dan berkelanjutan, mulai dari agenda setting, disain, adopsi, implementasi dan keberlanjutan. Peta jalan itu tidak mudah untuk dijalankan karena terdapat beragam kepentingan dan struktur yang bisa membatasi atau menghambat prakarsa reformasi. Pilihan dan tindakan (inisiasi, penyusunan proposal, kontestasi, pengeloaan konflik dan penciptaan aktor baru) dibutuhkan untuk mengelola beragam aktor dan kepentingan, sekaligus melakukan political crafting untuk melembagakan reformasi yang berhasil dan berkelanjutan. 33 Bagan 1.1 Proses dan institusionalisasi reformasi Arena Kepentingan & institusi institusi Agenda Disain Adopsi Struktur kepentingan Peran kebijakan eksekutif Sistem partai Keterkaitan internasional Implementasi Relasi pemerintah -masyarakat Relasi kementerian-masyarakat Relasi partai-masyarakat Kepentingan birokrasi Keberlanjutan Karakteristik pelaksana Struktur antarpemerintahan Kepentingan baru Inisiasi Proyek Reformasi Motivasi pemimpin Strategi pemimpin Pilihan & tindakan Susun Proposal Disain tim, jaringan pembaharu, strategi pembaharu Kontestasi Reformasi Karakteristik kebijakan, keluhan dan strategi oposisi, strategi pembaharu Mengelola konflik Strategi pemimpin & Strategi oposisi Menciptakan aktor baru Insentif dan aliansi Sumber: M. Grindle, Despite the Odds: The Contentious Politics of Education Reform, Princeton: Princeton University Press, 2004. ****** 34 Apa dan bagaimana relevansi reformasi yang digerakkan oleh masyarakat di atas dengan drama reformasi di Jembrana? Pertama, perspektif politik representasi masyarakat merebut negara mempunyai relevansi di Jembrana. IGW adalah orang biasa, bukan elite berkasta tinggi bukan pula warisan Orde Baru; tetapi trajektori politik IGW dimulai dari gerakan masyarakat sipil (LSM) yang menantang penguasa. Ia membawa reformasi dan sukses merebut kekuasaan pada tahun 2000. Kehadiran IGW, sebagai politisi-aktivis, dalam pemerintahan lokal Jembrana mempunyai signifikansi terhadap reformasi. Kedua, gerakan masyarakat menjadi elemen penting dalam trajektori politik dan drama reformasi Jembrana selama sepuluh tahun. Ketika IGW berkuasa, gerakan sosial masyarakat memang tidak menjadi penggerak reformasi, tetapi mereka mengkondisikan pertarungan politik yang memicu IGW melancarkan reformasi. Ketika IGW sangat kuat dan dominan pada tahun 2005, gerakan masyarakat tiarap, karena tidak mempunyai basis legitimasi dan dukungan dari publik. Ketika mereka tiarap, IGW melakukan korupsi. Ketika IGW melakukan korupsi, gerakan masyarakat bangkit kembali. Dengan legitimasi dan dukungan yang kuat, mereka bergerak melawan korupsi IGW serta mendelegitimasi dan meruntuhkan kekuasaannya. Ketiga, teori kekuasaan elite dan perspektif “reformasi untuk kekuasaan” memiliki relevansi terhadap trajektori politik dan drama reformasi Jembrana. Teori kekuasaan elite mempunyai relevansi secara parsial. Sebagai penguasa, IGW juga melakukan cara-cara tradisional seperti buju rayu, suap, konsesi, transaksi, koersi dan kooptasi. Namun cara-cara itu tidak semata untuk membangun kekuasaan, tetapi juga untuk melicinkan reformasi, misalnya IGW merebut APBD dengan cara transaksi dan konsensi kepada DPR. Reformasi tentu mempunyai andil yang lebih besar bagi IGW untuk memukul lawan-lawan politiknya, mendongkrak legitimasi dan dukungan rakyat, dan mendominasi kekuasaan. Keempat, perspektif “kekuasaan untuk reformasi” yang tercermin dalam reformasi yang digerakkan oleh elite, sangat dominan dalam bangunan reformasi 35 di Jembrana. Bupati IGW adalah tokoh sentral dalam reformasi Jembrana. Ia juga menerapkan kalkulasi politik, meskipun berbeda dengan mainstream kalkulasi teori aktor rasional. Jika teori aktor rasional mengutamakan ongkos besar, manfaat besar dan risiko kecil, tetapi IGW memilih pertarungan ganda (reformasi dan kekuasaan) yang membutuhkan ongkos besar, manfaat besar tetapi rentan, serta berisiko besar. Sementara perspektif pelembagaan reformasi juga relevan untuk melihat reformasi Jembrana, mulai dari sisi agenda setting, kalkulasi, disain kebijakan, kontestasi, pemenangan dukungan, hingga pelembagaan dan implementasi reformasi. Namun demikian, perspektif institusionalisasi reformasi yang bersifat linear itu tidak menangkap wajah audacious reform yang ditempuh IGW maupun dimensi “reformasi untuk kekuasaan”. Perspektif aktor rasional dan institusional juga tidak mampu secara sempurna menjawab pertanyaan mengapa reformasi Jembrana membuahkan kesuksesan gemilang tetapi kemudian mengalami kegagalan dan keruntuhan. Jika menggunakan teori kalkulus aktor rasional, reformasi Jembrana gagal karena menyimpang dari kalkulasi rasional. Seharusnya dengan kalkulasi ongkos besar, manfaat besar dan risiko kecil, tetapi kalau menyimpang dengan skema ongkos besar, manfaat tidak pasti, dan risiko tinggi, maka reformasi akan gagal. Kalau menggunakan teori elite, meskipun tidak mengenal reformasi, orang bisa mengatakan bahwa reformasi mengalami kegagalan karena Bupati IGW melakukan pembajakan terhadap reformasi. Sementara teori aksi kolektif memandang kegagalan reformasi Jembrana karena Bupati IGW menjadi “penumpang gelap” atas reformasi yang dia ciptakan sendiri, atau menikmati keuntungan pribadi di balik reformasi. Namun penjelasan dua perspektif itu terlalu singkat dan parsimonis, tidak melihat secara dalam bagaimana proses, konteks dan pertarungan di balik pembajakan atau pencarian keuntungan. Perspektif institusional melihat kegagalan reformasi lebih kompleks. Pertama, reformasi tidak didukung oleh legitimasi dan akuntabilitas yang kuat. Kedua, pemimpin reformasi gagal mengelola beragam kepentingan banyak aktor. 36 Ketiga, pemimpin reformasi bersikap eksklusif yang tidak membuka kesempatan stakeholder yang lebih luas. Keempat, disain kebijakan yang salah. Kelima, pemimpin reformasi gagal melakukan institusionalisasi secara sempurna, antara lain tidak melakukan deliberasi, negosiasi dan crafting dengan baik. Pada prinsipnya perspektif institusional itu hanya melihat dari sisi kekuasaan untuk reformasi. Grindle sudah mulai menyebut contentious politics dalam proses reformasi, tetapi ia tidak melihat dimensi “reformasi untuk kekuasaan” dan juga pertarungan kekuasaan yang berhimpitan dengan pertarungan reformasi. Dilihat dari sisi aktor, tentu tidak hanya hadir aktor pembawa reformasi, pendukung dan penentang atas reformasi, tetapi juga ada pendukung dan penentang kekuasaan. D.2. Perspektif Alternatif: Contentious Reform Paparan di atas telah menunjukkan dialog antara pengalaman Jembrana dan perspektif teori. Tidak ada teori tunggal yang mampu menjawab kisah Jembrana. Dari paparan itu pengalaman drama reformasi Jembrana mengandung gerakan sosial masyarakat, prakarsa reformasi oleh pemimpin, hasrat kekuasaan elite, insentif dan keberanian elite melakukan reformasi, perebutan kekuasaan, pelembagaan reformasi, penggunaan kekuasaan untuk melancarkan reformasi, dan juga penggunaan reformasi untuk membangun kekuasaan. Dengan kalimat lain, trajektori politik Jembrana selama 10 tahun mengandung “kekuasaan untuk reformasi” dan juga “reformasi untuk kekuasaan”. Karena anomalie itu, penulis berupaya meminjam dua teori, yaitu contentious politics dan teori strukturasi (agensi-struktur), untuk mengantarkan pemahaman dan penjelasan atas seluruh pertanyaan penelitian. Penulis akan mengelaborasi kedua teori itu, dan penulis berkepentingan untuk membangun “teori himpunan” antara kedua teori tersebut agar memiliki relevansi untuk deskripsi dan ekplanasi terhadap drama reformasi Jembrana. 37 D.2.1. Contentious Politics Studi ini diilhami oleh teori pertarungan politik (contentious politics), yang berguna untuk memahami dan menjelaskan contentious reform ala Jembrana. Doug McAdam, Sidney Tarrow, dan Charles Tilly – atau mereka menyebut sebagai McTeam-- adalah pencetus teori contentious politics setelah mereka melakukan evolusi yang panjang bersama teori gerakan sosial. Charles Tilly sebenarnya perintis awal yang kemudian direkonstruksi dan dikembangkan bersama dua koleganya, Doug McAdam dan Sidney Tarrow. Ketika masih menekuni perspektif proses politik dalam gerakan sosial pada tahun 1980-an hingga 1990-an, Charles Tilly belum memperkenalkan konsep teori contentious politics, kecuali hanya menggunakan konsep “peristiwa pertarungan” (contentious events) yang dia munculkan dalam dua karyanya (1986 dan 1995), masing-masing mengungkap sejarah pertarungan dalam Revolusi Perancis dan pertarungan massal di Inggris Raya pada masa Revolusi Industri. Karya terkemuka Sydney Tarrow, Power in Movement (1994, edisi pertama), juga belum memperkenalkan konsep contentious politics. McTeam mulai merayakan konsep contentious politics pada karya mereka tahun 1996, disusul karya Sydney Tarrow pada tahun yang sama. Jika karya Sydney Tarrow (1994) menekankan proses politik dalam gerakan sosial, karya revisi 1998 memasukkan gerakan sosial ke dalam contentious politics. Charles Tilly (1999) juga mulai menggunakan konsep contentious politics. Tahun-tahun berikutnya McTeam maupun Charles Tilly dan Sydney Tarrow secara sendirian maupun berdua terus memperkaya teori contentious politics (Charles Tilly, 2006, 2008; Charles Tilly dan Sydney Tarrow, 2006; Sydney Tarrow dan Charles Tilly, 2007; Doug McAdam, Sidney Tarrow, dan Charles Tilly, 2009; Sydney Tarrow, 2012), sembari mereka menggunakan teori itu untuk menganalisis gerakan sosial, perang sipil, revolusi, terorisme maupun demokratisasi (Charles Tilly, 2004; Sydney Tarrow, 2005; Doug McAdam, Sidney Tarrow, dan Charles Tilly, 2001). McTeam (2009) menegaskan bahwa contentious politics merupakan teori himpunan dari berbagai perspektif gerakan sosial generasi 1970-an hingga 1990- 38 an seperti perspektif pilihan rasional, perspektif proses politik, perspektif mobilisasi sumberdaya, dan perspektif organisasi gerakan sosial. Karya Sydney Tarrow satu dekade sebelumnya telah menekankan bahwa gerakan sosial merupakan alur politik pertarungan yang berbasis pada jaringan sosial dan kerangka aksi kolektif, dan yang mengembangkan kapasitas merawat keberlanjutan menentang musuh-musuh yang kuat (Sydney Tarrow, 1998). Kemudian McTeam mendefinisikan contentious politics sebagai interaksi kolektif yang bersifat publik dan episodik di antara pembuat klaim dan obyek-obyek mereka ketika (a) pemerintah menjadi obyek yang diklaim, atau pihak yang melakukan klaim (b) klaim jika direalisasikan akan berdampak terhadap kepentingan paling tidak satu pihak yang diklaim (Doug McAdam, Sidney Tarrow, dan Charles Tilly 2001; Charles Tilly, 2004). Mereka menyederhanakan definisi itu menjadi “perjuangan politik kolektif”. Para sarjana di luar McTeam, sekaligus kritikus teori contentious politics, umumnya menunjukkan tidak adanya perbedaan antara gerakan sosial dan contentious politics. Antara gerakan sosial dan contentious politics saling dipertukarkan (Mark I. Lichbach, 1998; Karen Stanbridge, 2006; David S. Meyer dan Daisy Verduzco Reyes, 2010). Gerakan sosial merupakan bentuk contentious politics dan contentious politics mengandung gerakan sosial. Dalam merespons berbagai kritik, McTeam menegaskan bahwa contentious politics bukan sekadar gerakan sosial dan bukan sekadar politik yang rutin. Contentious politics lebih sempit daripada politik dalam pengertian umum. Namun tidak semua politik mengandung contentious. Upacara, proses birokrasi, pengumpulan informasi, kegiatan pendidikan, dan lain-lain merupakan bentukbentuk kehidupan politik rutin sehari-hari yang tidak termasuk contentious politics (Charles Tilly dan Sydney Tarrow, 2007). Selain itu tidak semua gerakan sosial sebagai contentious politics. Contentious politics lebih besar daripada gerakan sosial karena di dalamnya mengandung politik. Dalam karya terbarunya, Sydney 39 Tarrow (2012) menegaskan bahwa episode pertarungan politik jauh lebih luas daripada kampanye gerakan sosial. Sejak 2007 McTeam, khususnya karya-karya Charles Tilly dan Sydney Tarrow, semakin memantapkan teori contentious politics. Definisi awal dalam karya McTeam (2001, 2004) dielaborasi lebih jauh, dengan penekanan bahwa contentious politics mengandung tiga komponen (pertarungan, aksi kolektif dan politik) seperti terlihat dalam bagan 1.2. Pertama, komponen pertarungan (contention), yakni satu pihak (subyek) membuat klaim atas pihak lain (obyek). Kedua, aksi kolektif merupakan koordinasi upaya atas nama kepentingan dan tujuan bersama. Ketiga, politik berarti ada proses interaksi dengan pemerintah, yakni menantang kewenangan, regulasi dan kepentingan pemerintah. Bagan 1.2 Kerangka contentious politics Contentious Politics Pertarungan Politik Aksi kolektif Sumber: Charles Tilly dan Sydney Tarrow, Contentious Politics (Boulder CO: Paradigm Publisher, 2007), hal. 7. Jika politik konvensional mengenal institusi, McTeam menggunakan mekanisme (mechanism) – yang dalam sosiologi klasik disebut sebagai proses sosial dalam struktur-sistem sosial – untuk membingkai teori contentious politics. 40 Mereka mendefinisikan mekanisme sebagai berikut: rangkaian peristiwa terbatas yang mengubah hubungan antara sekumpulan elemen spesifik dengan cara yang mirip atas beragam situasi. Definisi ini sungguh sulit untuk dipahami. J. Mahoney (2001) pernah mengidentifikasi sejumlah 24 definisi yang berbeda-beda tentang mekanisme, dan karena itu membingungkan. Ada beberapa definisi lain yang sederhana dan membantu untuk memahami mekanisme. M. Bunge (1997) menyebut mekanisme sebagai sebuah proses dalam sistem yang konkret, dimana sistem adalah hubungan antarlemen yang saling tergantung. R. Mayntz (2004) mendefinisikan mekanisme sebagai proses pengulangan (recurrent process) yang menghubungkan antara kondisi awal dan hasil spesifik. J. Elster (1998) menyomot metafora “jeruji dan roda” untuk memahami mekanisme. McTeam (Doug McAdam, Sydney Tarrow dan Charles Tilly, 2004 dan 2009; Charles Tilly, 2004; Sydney Tarrow dan Charles Tilly, 2007; Charles Tilly dan Sydney Tarrow, 2007; Sydney Tarrow, 2012) lalu mengidentifikasi tiga bentuk mekanisme dalam contentious politics. Pertama, mekanisme lingkungan (environmental mechanism): pengaruh eksternal atas kondisi yang membentuk kehidupan sosial. Sebagai contoh, penguatan sumberdaya mempengaruhi kapasitas orang untuk terlibat dalam pertarungan politik. Kedua, mekanisme disposisional yang mencakup perubahan perspepsi, cara pandang, tindakan individu maupun kolektif. Ketiga, mekanisme relasional mencakup perubahan hubungan antara orang, kelompok dan jaringan interpersonal. Dalam konteks ini kehadiran perantara disebut sebagai mekanisme relasional, yang menghubungkan aktor satu dengan aktor lainnya, serta untuk mobilisasi sumberdayan selama episode pertarungan politik. Studi ini berupaya mengadaptasi sebagian komponen dalam teori politik pertarungan, sekaligus juga memodifikasinya agar relevan untuk memahami dan menjelaskan drama contentious reform di Jembrana. Ada sejumlah argumen penting yang penulis sampaikan. 41 Pertama, studi ini tidak mengambil narasi besar teori pertarungan politik yang berpusat pada gerakan sosial yang masuk dalam ranah pertarungan, melainkan mengambil narasi kecil teori pertarungan politik. Narasi kecil itu adalah konsep “peristiwa pertarungan” (contentious events) yang diperkenalkan pertama kali oleh Charles Tilly pada tahun 1986, atau konsepsi McTeam tentang perjuangan politik (political struggle). Sejumlah studi sebenarnya juga telah mengadaptasi teori pertarungan politik dalam pengertian dan skope narasi kecil itu. M. Hanagan, L. Moch dan W. Brake (1998) memaknai pertarungan politik secara sederhana sebagai interaksi timbal balik antara pemerintah sebagai subyek pemegang kekuasaan-kewenangan dengan masyarakat yang berposisi sebagai obyek kekuasaan-kewenangan. Thomas Maher dan Lindsey Peterson (2008), tanpa melakukan elaborasi narasi besar teori contentious, memahami pertarungan politik dalam bentuk interaksi perlawanan massa dengan represi penguasa. Dan Slater (2010) memahami pertarungan politik sebagai konflik, yang antara lain hadir dalam bentuk konflik sosial, konflik kelas, konflik internal, mobilisasi massa dan perang sipil, yang semua itu merupakan subtipe pertarungan yang berada di bawah payung besar contentious politics. A. Oberschall (2010) memahami pertarungan politik sebagai klaim politik kolektif yang berdampak terhadap kepentingan musuh. Tuong Vu (2006), melalui studi tentang pertarungan politik berbasis massa di Asia Tenggara, melakukan penyimpangan dari definisi politik pertarungan ala McTeam, seraya menawarakan definisi politik pertarungan sebagai politik yang tidak terlembaga yang melibatkan nonelite dan sebuah kontestasi untuk kekuasaan atau kewenangan dalam masyarakat-negara (polity) tetapi tidak selalu bersifat publik dan kolektif. Pemahaman tentang contentious politics dari beberapa studi itu sungguh memberikan ilham studi ini. Namun yang paling berpengaruh terhadap studi ini adalah studi M. Grindle (2004), yang menggunakan narasi kecil contentious politics – tanpa mengutip teori contentious politics ala McTeam -- untuk menganalisis politik reformasi pendidikan di Amerika Latin. Bagi Grindle, reformasi pendidikan 42 bukan sekadar perkara administrasi dan teknokrasi, tetapi mengandung pertarungan politik antara pencetus (penggerak) reformasi yang memobilisasi pendukung secara luas melawan aktor-aktor penentangnya. Kedua, pertarungan politik merupakan peristiwa politik yang tidak biasa, nonrutin, nonlinear dan nonkonvensional. Upacara, konsultasi, kunjungan kerja, pemilihan umum, pilkada, musrenbang, dan lain-lain termasuk bentuk-bentuk politik biasa yang rutin dan konvensional. Sementara reformasi merupakan salah satu bentuk politik yang tidak biasa, nonrutin, nonkonvensional, yang sarat dengan pertarungan. Drama contentious reform di Jembrana menggambarkan politik nonrutin yang mengandung pertarungan. Namun bukan berarti politik Jembrana selama satu dekade berwajah contentiuous secara keseluruhan, dan contentious reform bukan berarti merupakan drama politik Jembrana secara total. Selain ada drama contentious reform, politik rutin juga tetap berjalan. Aksi kolektif melawan bupati terkadang hadir dan pergi, tetapi rutinitas tetap berjalan, termasuk kunjungan kerja dan studi banding dari tempat lain ke Jembrana. Ketiga, pertarungan politik tidak sepenuhnya hadir dalam bentuk aksi kolektif komponen nonpemerintah maupun massa dalam bentuk gerakan sosial, terorisme, perang sipil maupun revolusi menentang dan melawan penguasa. Studi ini menekankan interaksi timbal balik dan kompleks diantara beragam aktor: masyarakat, birokrasi, politisi dan bupati. Pertarungan politik dapat hadir dalam bentuk aksi kolektif masyarakat menantang politisi maupun bupati, bisa juga dalam bentuk koalisi partai melawan birokrasi dan bupati, atau bisa juga aksi para birokrat melawan penguasa. Sebaliknya pertarungan bisa muncul dari bupati. Penulis berpendapat bahwa reformasi yang dilancarkan bupati merupakan pilihan dan tindakan yang membuka pertarungan politik, yang menantang komponen birokrasi, politisi dan bahkan masyarakat. Keempat, pertarungan politik bersifat episodik. Proses pertarungan politik berjalan dalam rangkaian repertoire (alur dan penggalan) laksana drama yang mengalir dalam banyak babak (episode) secara dinami, dialektik dan spiral: ada 43 proses pengulangan, kemajuan dan kemunduran, kesuksesan dan kegagalan, serta banyak kejadian dan kejutan yang tidak terbayangkan. Penulis meminjam term episodik ini membuat narasi tentang drama reformasi di Jembrana yang terdiri dari banyak babak, mulai dari babak kesatu (melawan penguasa, merebut kekuasan), babak kedua (konsolidasi kekuasaan, inisiasi reformasi), babak ketiga (meraih kejayaan kekuasaan dan reformasi); dan babak keempat (krisis reformasi, keruntuhan kekuasaan). Dalam setiap babak mengandung pertarungan politik yang kompleks, dinamis, nonlinear dan bahkan dramatis. Kesuksesan reformasi dan kejayaan kekuasaan IGW yang menggumpal pada tahun 2003 hingga 2008; dan akhirnya berbuntut pada keruntuhan reformasi dan kekuasaan pada tahun 2009-2010, sungguh mencerminkan pola pertarungan yang episodik-spiral itu. Namun pertarungan episodik itu tidak sepenuhnya bersifat publik dan terbuka. Selain publik, pertarungan politik dapat berbentuk privat. Politik privat pada dasarnya merupakan interaksi kolektif parapihak yang mengutamakan kepentingan mereka dengan tidak tergantung pada hukum, tatanan publik atau negara (David Baron, 2003). Dalam masyarakat Indonesia, biasa terjadi konflik privat berdampak terhadap konflik publik, dan konflik publik bisa dibawa ke ranah konflik privat. Studi ini menunjukkan konflik privat yang berkembang menjadi pertarungan publik. Sebagai contoh adalah ketegangan personal antara Bupati IGW dengan seorang tokoh bernama IGN Ngurah Hartono, yang berdampak terhadap aksi perlawanan publik Hartono melawan kekuasaan IGW. Di sisi lain, pertarungan politik tidak selalu berjalan secara terbuka dalam ruang publik (di depan layar), tetapi bisa juga berbentuk pertarungan bawah tanah (underground politics) atau di balik layar. Kelima, konsep mekanisme sebagai bingkai pertarungan politik juga memberikan ilham bagi studi ini. Drama reformasi tentu tidak bekerja dalam mekanisme institusional, namun ia juga tidak sepenuhnya bekerja dalam bingkai mekanisme dan proses semata. Institusi (kultur, nilai, visi, kebijakan, aturan main, prosedur, tatakelola dan lainnya), mekanisme dan proses membentuk dan 44 menjadi bingkai pertarungan politik. Proses menunjuk pada tindakan, peristiwa, relasi, maupun alur dalam drama contentious reform. Sedangkan mekanisme menunjuk pada interaksi atau jalinan sejumlah elemen dalam pertarungan. Hubungan antara proses dan mekanisme ibarat hubungan antara telur dan ayam. Mekanisme melahirkan proses, dan proses membentuk mekanisme. Secara konkret interaksi tiga elemen penting (aksi kolektif, pertarungan dan politik) seperti tergambar dalam bagan 1.2 merupakan bentuk mekanisme, seperti halnya interaksi jeruji, velg dan roda dan perputaran roda. Dalam studi ini penulis mengadaptasi tiga elemen contentious politics (aksi kolektif, pertarungan dan politik) dan tiga mekanisme (lingkungan, disposisional dan relasional) untuk memahami dan menjelaskan drama reformasi di Jembrana. Namun adaptasi itu tidak penulis lakukan secara total, sebab teori McTeam cenderung mengabaikan komponen institusi, dan hanya menekankan pertarungan satu arah, yakni dari penentang -- atau sebagai “orang asing di pintu gerbang” jika meminjam istilah Sydney Tarrow (2012) – melawan penguasa. Mark Lichbach dan Helma De Vries (2007) telah mengingatkan tiga level pertarungan politik yang perlu diperhatikan oleh pengguna teori contentious politics: (a) level makro yang berbicara tentang konteks budaya ekonomi politik yang melingkupi pertarungan politik; (b) level meso yang mencakup struktur kesempatan politik bagi aksi kolektif; dan (c) level mikro: motif, insentif dan tindakan yang membawa aktor dalam pertarungan, termasuk sumberdaya, komitmen dan jaringan mereka. Teori contentious politics di atas mengantarkan pemahaman bahwa pertarungan politik bisa terjadi secara bersamaan di ranah reformasi (kekuasaan untuk reformasi) dan di ranah kekuasaan (reformasi untuk kekuasaan). Pertarungan di dua ranah ini tidak hanya menghasilkan aktor pembawa reformasi beserta pendukung dan penentang reformasi, juga menghadirkan pemegang kekuasaan beserta pendukung dan penentang kekuasaan. Setiap aktor mempunyai kepentingan, sikap, cara pandang, preferensi dan afiliasi yang berbeda-beda 45 terhadap kekuasaan dan reformasi. Bagan 1.3 memberikan peta tipologis tentang sikap politik aktor terhadap kekuasaan dan reformasi. Pertama, kelompok konformis atau kelompok liberal bersikap menerima kekuasaan dan menerima reformasi. Kedua, kelompok konsevatif bersikap menerima kekuasaan tetapi menolak (anti) reformasi. Ketiga, kaum radikal bersikap menerima reformasi tetapi menolak (anti) kekuasaan. Keempat, kelompok reaksioner bersikap menolak kekuasaan dan menolak reformasi. Bagan 1.3 Tipologi sikap politik terhadap kekuasaan dan reformasi Sikap terhadap kekuasaan Menerima Menolak Menerima Konformis Radikal Menolak Konservatif Reaksioner Sikap terhadap reformasi Sumber: Diadaptasi dan dimodifikasi dari Mohtar Mas’oed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, Jakarta: LP3ES, 1991, hal. 112. Teori contentious politics bersifat fleksibel, bisa dimaksukkan dalam kerangka kekuasaan dan bisa juga ditempatkan dalam kerangka reformasi. Karena berangkat dari tema reformasi, studi ini memilih kerangka reformasi ketimbang kerangka kekuasaan. Penulis akan menggabungkan antara teori contentious politics dengan model reformasi, yang akan menghasilkan contentious reform, pada uraian di bawah ini. 46 D.2.2. Model Reformasi Model reformasi merupakan alat deskripsi dan eksplanasi yang berangkat dari sejumlah pertanyaan. Siapa yang melakukan reformasi? Bagaimana proses dan hasil reformasi? Apakah perbedaan aktor pendorong dan proses reformasi mempengaruhi perbedaan hasil reformasi? Bagaimana kekuasaan bermain dalam reformasi? Bagaimana memahami reformasi yang berhasil sementara, reformasi yang berhasil dengan gemilang, kokoh dan berkelanjutan, serta reformasi yang rentan, gagal dan tidak berkelanjutan? Tabel 1.2 Dinamika pasca reformasi Investasi Kelompok SEDERHANA (Aktor-aktor sosial politik gagal melakukan investasi berskala besar; adaptasi organisasional untuk melakukan reformasi sangat minimal) EKSTENSIF (Kelompok-kelompok membuat investasi berskala besar, sering berbentuk investasi spesifik yang tinggi berbasis pada harapan bersama bahwa reformasi akan berlanjut) Identitas dan Afiliasi Kelompok STABIL CAIR (Identitas dan afiliasi (Kelompok-kelompok baru kelopok relatif stabil, muncul, koalisi cepat banyak pengikut memiliki berubah, kohesi kelompok preferensi kebijakan yang kepentingan lemah) sama) Pembalikan Reformasi Erosi Reformasi Reformasi kokoh dan berkelanjutan Rekonfigurasi, hasil reformasi ditata ulang Sumber: Eric M. Patashnik, Reforms at Risk: What Happens After Major Policy Changes Are Enacted, Princeton: Princeton University Press, 2008. Eric M. Patashnik (2008) memberikan kontribusi yang berharga dalam menganalisis dinamika pascareformasi, sebagaimana tersaji dalam tabel 1.2. Patashnik membuat tipologi dinamika pascareformasi dengan dua variabel 47 penting: identitas dan afiliasi kelompok serta investasi kelompok. Identitas dan afiliasi kelompok ia bagi menjadi dua: stabil (Identitas dan afiliasi kelopok relatif stabil, banyak pengikut memiliki preferensi kebijakan yang sama) dan cair (kelompok-kelompok baru muncul, koalisi cepat berubah, kohesi kelompok kepentingan lemah). Empat tipe hasil pasca reformasi itu sangat menarik untuk diadaptasi, tetapi masih perlu elaborasi lebih lanjut tentang dinamika proses reformasi, relasi antaraktor dan juga pertarungan politik yang melingkupi reformasi. Untuk itu dibutuhkan model-model reformasi yang bisa memberikan jawaban lebih memadai dan melengkapi tipologi karya Eric Patashnik. Penulis mengadaptasi cara pandang Adrienne Heritier (2007) yang mengidentifikasi dua perspektif atau model perubahan institusional (reformasi). Pertama, model proses reformasi, yang mencakup jalur reformasi, aktor atau kekuatan-kekuatan pendorong reformasi, sebab akibat dan hasil reformasi, serta mengidentifikasi tipe sekuen-sekuen khas perubahan. Kedua, model struktural reformasi, yang mencakup proses reformasi, level dan arena reformasi, interaksi dan kontestasi antaraktor, penggunaan kekuasaan, tipe organisasi dan aktor-aktor yang terlibat dalam proses reformasi, serta tipe dan hasil reformasi. Model proses selalu digunakan para analis dalam memahami jalur reformasi, apakah “reformasi dari bawah” (reform from bellow) yang digerakkan oleh masyarakat (society driven reform), yang juga sering disebut sebagai demand side reform, atau reformasi dari atas (reform from above) yang digerakkan oleh elite (elite driven reform atau elite led reform), yang memiliki kesamaan dengan supply side reform.2 Berbeda dengan cara pandang “reformasi dari atas” dan 2Lihat misalnya Susan E. Scarrow, “Direct Democracy and Institutional Change: A Comparative Investigation”, Comparative Political Studies, 34; 651, 2001; Kurt Weyland, “Toward a New Theory of Institutional Change, World Politics, No. 60, Januari 2008; Christopher W. Close, The Negotiated Reformation: Imperial Cities and the Politics of Urban Reform, Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 48 “reformasi dari bawah” ini, Alan Renwick melihat jalur dan kekuatan penggerak reformasi yang berasal “dari dalam” (endogen) dan reformasi dari luar (eksogen).3 Berdasarkan varian tentang kekuatan (aktor) dan jalur reformasi (reformasi dari atas dan reformasi dari bawah serta reformasi dari dalam dan reformasi dari luar) itu penulis melakukan rekonstruksi model proses reformasi yang secara interaktif dan tipologis tersaji dalam bagan 1.4. Kuadran I (reformasi elitis) menggambarkan proses reformasi yang bekerja dari atas dan dari dalam, yang tidak menyertakan unsur-unsur di luar elite dan pemerintah daerah. Proses ini terjadi ketika organisasi masyarakat sipil dalam posisi lemah yang tidak mengambil inisiatif reformasi, atau di dalam elite sendiri terjadi proses kompetisi dan negosiasi atas reformasi. Kuadran II (rekayasa teknokratis) menyajikan reformasi yang terbatas, menggunakan keahlian teknokratis dari pihak luar, yang dipakai oleh penguasa. Proses ini tidak melibatkan engagement antara penguasa dengan politisi, melainkan hanya membuat kebijakan baru yang dilembagakan dalam tubuh pemda dan birokrasi. Kuadran III (reformasi partisipatoris konsensual) menggambarkan proses reformasi yang ditempuh melalui deliberasi dan negosiasi secara internal (pemda, DPRD dan birokrasi) maupun secara eksternal antara pemda, politisi dan masyarakat. Proses ini berlangsung kritis, terbuka dan elegan yang membuahkan keputusan kolektif untuk reformasi. Kuadran IV (aksi kolektif atau gerakan sosial) adalah proses reformasi yang digerakkan oleh kekuatan dari luar bersama organisasi masyarakat dari bawah. Pola ini bisa muncul ketika jajaran elite, DPRD, birokrasi dalam posisi yang lembam, konservatif dan bahkan penuh dengan KKN. Dalam konteks demokratisasi, pola aksi kolektif ini disebut dengan jalur replacement atau rupture yang menjatuhkan dan menggantikan penguasa otokratis, seperti pengalaman jatuhnya Soeharto pada tahun 1998. 3Adrienne Heritier, Explaining Institutional Change in Europe, Oxford: Oxford University Press, 2007 dan Alan Renwick, The Politics of Electoral Reform: Changing the Rules of Democracy, Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 49 Model kedua, adalah model struktural, menggambarkan tentang penggunaan kekuasaan dalam reformasi, pertarungan antaraktor dalam reformasi, pertarungan antara reformasi dan kekuasaan; tindakan aktor dalam menghadapi regulasi; serta sifat, tujuan dan hasil reformasi. Berdasarkan “model struktural” ini penulis membagi ada empat bentuk reformasi seperti terlihat dalam tabel 1.3. Pertama, incremental reform, sebuah reformasi yang pelan-pelan, bertahap, dan tidak penuh dengan kejutan-kejutan politik. Model ini bisa juga disebut dengan transformasi jangka panjang melalui inovasi yang berlangsung terus-menerus. Elite politik dan jajaran teknokrat-birokrat adalah pelaku utama yang menggerakkan reformasi. Jajaran elite ini secara hati-hati merespons regulasi, sekaligus mengelola kekuasaan secara hati-hati agar tidak menimbulkan gejolak yang serius. Bagan 1.4 Model “proses” reformasi Dari atas: elite II: Dari luar: donor, NGOs luar, akademisi, konsultan, aktoraktor di balik layar Dari dalam: (Pemda, DPRD, birokrasi) Dari bawah: organisasi masyarakat, massa Kedua, smart reform atau institutionalized reform, yakni terjadi perubahan institusional secara cerdas dengan pendekatan win-win solutions. Dalam model ini, terjadi kompetisi-kontestasi yang dinamis antaraktor politik, 50 terjadi titik temu antara desakan (demand) dari bawah dan kehendak atau supply dari atas. Dengan kalimat lain, beragam aktor duduk bersama melakukan deliberasi dan negosiasi untuk melahirkan visi dan agenda reformasi, sehingga hampir tidak ada kepentingan aktor yang terganggu atau dirugikan. Karena itu model ini identik dengan kombinasi antara identitas dan afiliasi kelompok yang bersifat stabil dan investasi kelompok yang bersifat ekstensif, sehingga membuahkan reformasi yang sukses, kokoh dan berkelanjutan, meskipun proses politik membutuhkan waktu panjang dan energi yang besar. Tabel 1.3 Model “struktural” reformasi Incremental Reform Smart Reform Audacious Reform Contentious Reform Makna Inovasi yang pelanpelan bertahap Reformasi yang dilakukan dengan nekat dan cepat Aktor penggerak Elite atau teknokrat dan birokrat Kalkulasi rasional Ongkos kecil, manfaat kecil, risiko kecil. Kekuasaan digunakan secara minimalis, dikelola secara hati-hati dan tidak menimbulkan gejolak Perubahan institusional secara smart dan win-win. Elite penguasa dan/atau oposisi atau aksi kolektif masyarakat sipil Ongkos besar, manfaat besar, risiko kecil Kekuasaan digunakan secara optimal untuk reformasi, terjadi kontestasi dan negosiasi antaraktor Terjadi titik temu (engagement) dan crafting antara demand side pressure dan supply side pressure. Kekuasaan digunakan untuk reformasi, reformasi digunakan kekuasaan Elite penguasa dan/atau organisasi oposisi yang saling bertarung Ongkos besar, manfaat/hasil tidak pasti, risiko besar Antara kekuasaan dan reformasi saling mempengaruhi dan saling bertarung (contentious) Kekuasaan Relasi antaraktor Kesuksesan dan keberlanjutan Terjadi proses kompetisi dan negosiasi internal di kalangan elite. Tidak ada desakan (demand) dan perlawanan dari masyarakat Kesuksesan bersifat parsial, atau kesuksesan jangka panjang Sukses, kokoh dan berlanjut 51 Elite penguasa Ongkos kecil, manfaat besar, risiko besar Kekuasaan digunakan secara nekat untuk menembus rintangan-rintangan reformasi Penggerak reformasi tidak peduli dengan aktor-aktor penghambat. Ia melaju secara nekat karena yakin bahwa reformasi akan didukung rakyat Kesuksesan bersifat sementara, rentan atau sulit berlanjut. Pertarungan tiada henti antara penguasa dengan aktor-aktor politik lain. Kesuksesan dan kegagalan silih berganti. Keberlanjutan rentan Ketiga, audacious reform. Model ini penulis adaptasi dan modifikasi dari gagasan dan temuan M. Grindle (2000) dalam studinya tentang penemuan institusional dan demokratisasi di Amerika Latin. Grindle merumuskan tiga makna audacious reform: (1) aktor-aktor politik dengan nekat melakukan perubahan dan menciptakan aturan baru tentang distribusi kekuasaan yang sangat berisiko terhadap kekuasaan mereka; (2) perubahan tidak berlangsung secara inkremental-evolutif melainkan berlangsung secara dramatis; dan (3) perubahan membawa dampak terhadap perilaku politik, kompetisi politik dan insentif politik yang tidak dapat diantisipasi secara pasti. Konsep itu sungguh memberi ilham kepada penulis, tetapi penulis berupaya melakukan modifikasi gagasan Grindle agar bisa digunakan secara kontekstual. Dalam konteks ini, penguasa lokal seperti kepala daerah secara nekat dan dramatis melakukan perombakan terhadap struktur pemerintahan dan birokrasi, termasuk penganggaran, agar dengan cepat menciptakan distribusi kue pembangunan kepada rakyat banyak. Dengan semboyan “pukul dulu urusan belakang”, penguasa melancarkan audacious reform secara nekat menabrak regulasi dan tanpa payung regulasi yang akuntabel secara hukum, sebab dia mempunyai keyakinan kuat bahwa reformasi dimaksudkan untuk menjawab kehendak rakyat dan karena itu reformasi akan memperoleh dukungan dari rakyat, meskipun ditentang oleh kalangan elite. Cara reformasi yang nekat ini pasti menghadapi rintangan dan perlawanan dari kaum konservatif, reaksioner dan radikal, tetapi elite penggerak reformasi melaju terus dengan nekat, dengan semangat “anjing menggongong khafilah tetap berlalu”. Reformasi nekat membuahkan kesuksesan secara cepat, tetapi cenderung bersifat sementara dan tidak berkelanjutan. Ketika kekuasaan mengalami pergantian, dan penguasa penggerak reformasi lengser, maka akan terjadi pembaliklan reformasi ketika penguasa baru hadir. Warisan reformasi karya penguasa lama akan dirombak oleh penguasa baru. Keempat, contentious reform. Konsep dan model contentious reform ini merupakan gagasan dari penulis pribadi, yang berupaya menggabungkan antara 52 konsep contentious politics dengan reformasi. Jika dalam berbagai literatur ilmu politik ada contentious action, contentious politics, contentious democratization, contentoius history, contentious performances, contentious protest, dan juga contentious issues, kenapa contentious reform tidak bisa diciptakan. M. Grindle (2004) sebenarnya pernah mengadaptasi konsep contentious politics dalam reformasi pendidikan di Amerika Latin, namun dia hanya menunjukkan pertarungan, dalam bentuk kontestasi antaraktor dalam proses reformasi, dan tidak merekonstruksi contentious reform. Celah dan kesempatan inilah yang penulis manfaatkan untuk merumuskan contentious reform (reformasi penuh pertarungan). Dalam reformasi pasti terdapat pertarungan seperti dirumuskan dalam model audacious reform. Namun dalam model contentious reform, yang terjadi bukan sekadar pertarungan antara penggerak, pendukung dan penolak reformasi. Model contentious reform lebih kompleks daripada audacious reform. Dalam audacious reform hanya terjadi pertarungan kekuasaan untuk mencapai reformasi, tetapi dalam contentious reform, kekuasaan dan reformasi saling mempengaruhi, memanfaatkan dan saling bertarung. Cara pandang contentious politics menegaskan bahwa reformasi sarat dengan dilema: penguasa yang sukses melakukan reformasi cenderung mendominasi dan mengawetkan kekuasaan, bahkan menumpuk kekayaan, yang tidak terkontrol. Konteks politik yang kompetitif, bahkan penuh pertarungan (penuh dengan perlawanan kaum radikal dan reaksioner), akan membuat penguasa mengambil inisiatif reformasi. Kehendak dan agenda reformasi itu bisa melemahkan perlawanan kaum radikal dan reaksioner, sehingga kekuasaan penguasa lokal menjadi lebih kuat. Tetapi ketika kekuasaan menjadi kuat, dominatif dan tidak terkontrol, reformasi akan melemah dan kekuasaan itu menjadi korup. Dalam situasi seperti ini akan melahirkan perlawanan dari kaum radikal (mendukung reformasi tetapi menolak kekuasaan, misalnya melakukan gerakan antikorupsi) dan kaum reaksioner (yang 53 menolak kekuasaan dan menolak reformasi). Karena itu reformasi hanya sukses sementara, tetapi rentan dan tidak berkelanjutan. Kombinasi sejumlah bagan dan tabel di atas menghasilkan beberapa varian reformasi yang penulis rekonstruksi secara hipotetik: 1. Reformasi elitis tidak mungkin mengarah pada smart reform, melainkan condong mengarah pada incremental reform, audacious reform atau contentious reform. Reformasi elitis cenderung abai pada keterlibatan organisasi masyarakat sipil (OMS), atau memang OMS dalam kondisi yang lemah dan tidak mendorong reformasi. Proses reformasi model ini digerakkan oleh elite, bekerja dalam tubuh pemerintah daerah, birokrasi dan DPRD, sehingga hanya membuahkan reformasi incremental. Reformasi ini akan hadir dalam bentuk inovasi pelan-pelan dan gradual, ketika bekerja dalam situasi harmoni, sehingga tidak menimbulkan gejolak kekuasaan yang berarti. Dinamika pasca reformasi bisa mengarah pada pembalikan reformasi ketika terjadi pergantian kekuasaan, atau inovasi gradual tetap berjalan secara inkremental ketika pergantian kekuasaan juga berlangsung secara inkremental. 2. Reformasi elitis bisa mengarah pada audacious reform, ketika kehendak reformasi kepala daerah ditentang oleh aktor-aktor politik lainnya. Ia nekat menembus rintangan-rintangan reformasi, seraya melancarkan reformasi secara cepat dan dramatis. Hasil reformasi cenderung bersifat sementara dan tidak berkelanjutan, bahkan bisa terjadi pembalikan reformasi ketika telah terjadi pergantian kekuasaan. 3. Reformasi elitis bisa mengarah ke contentious reform ketika pertarungan dan perlawanan politik telah terjadi di babak awal. Penguasa melakukan reformasi dengan tujuan melemahkan dan menundukkan perlawanan politik, seraya membawa perubahan pemerintahan yang membuahkan kepercayaan dan legitimasi dari rakyat. Dukungan rakyat itulah yang melemahkan perlawanan kaum radikal dan reaksioner, sehingga kekuasaan penguasa menjadi lebih kuat dan dominatif. Ketika kekuasaan menjadi kuat, dominatif dan tidak terkontrol, 54 reformasi akan melemah dan kekuasaan itu menjadi korup. Kondisi ini akan disambut kembali perlawanan kaum reaksioner dan radikal. Identitas dan afiliasi kelompok menjadi cair, sementara investasi kelompok tetap sederhana dan terbatas, sehingga membuahkan erosi reformasi di penghujung kekuasaan penguasa. 4. Audacious reform bisa mengarah pada contentious reform, tetapi tidak semua audacious reform bisa berubah menjadi contentious reform. Audacious reform malah bisa mengarah pada institutionalized reform jika reformasi berjalan secara konsisten, memperoleh dukungan luas dari politisi maupun organisasi masyarakat sipil, sekaligus terjadi negosiasi dan konsolidasi yang kuat di antara mereka. Tetapi audacious reform akan mengarah pada contentious reform jika contentious politics terus berjalan, jika reformasi tetap digerakkan oleh penguasa semata tanpa dukungan luas, dan jika penguasa menggunakan reformasi untuk membangun kekuasaan. 5. Rekayasa teknokratis, seperti halnya reformasi elitis, tidak mungkin mengarah pada smart reform, melainkan hanya membuahkan incremental reform. Pola seperti ini akan tetap berkelanjutan ketika tidak ada desakan dan perlawanan yang berarti, baik di dalam lingkaran elite maupun dari masyarakat. Tetapi ketika terhadi kontestasi dan pertarungan, maka bisa mengarah pada contentius reform. 6. Reformasi partisipatoris-konsensual yang bekerja dalam konteks kontestasi politik yang dinamis dapat membuahkan smart reform atau institutionalized reform. Smart reform ini akan membuahkan kesuksesan dalam jangka pendek dan menghasilkan reformasi yang kokoh dan berlanjut dalam jangka panjang. Identitas dan afilisiasi kelompok yang stabil, serta investasi kelompok yang ekstensif, karena proses deliberasi dan negosiasi antaraktor dalam proses reformasi, mampu merawat keberlanjutan reformasi, meski terjadi pergantian kekuasaan. 55 7. Aksi kolektif, atau society led reform atau demand side reform, membuahkan beberapa kemungkinan, kecuali incremental reform dan audacious reform. Pertama, sama sekali tidak ada reformasi ketika aksi kolektif itu melemah atau ketika penguasa otokratis-konservatif melemahkan aksi kolektif dengan cara represi atau kooptasi. Kedua, terjadi smart reform ketika penguasa memberikan respons positif, yang mendorong penguasa dan pejuang reformasi duduk bersama, melakukan deliberasi dan negosiasi untuk melahirkan visiagenda reformasi secara kolektif. Jika hal ini terjadi maka reformasi akan kokoh dan berkelanjutan. Ketiga, terjadi contentious reform yang berbasis atau digerakkan masyarakat. Model ini mendorong terjadinya delegitimasi penguasa atau bahkan pemakzulan penguasa, yang berikutnya akan melahirkan penguasa baru yang akan melancarkan reformasi. Studi ini berargumen bahwa reformasi Jembrana bukanlah reformasi inkremental yang bekerja dengan rekayasa teknokratis dan berjalan secara gradual dalam ruang yang hampa politik. Reformasi Jembrana bukan juga sebagai institutionalized reform yang dihasilkan melalui negosiasi dan pakta sosial beragam aktor baik dari bawah maupun dari atas, apalagi reformasi Jembrana hanya membuahkan keberhasilan secara temporer dan akhirnya mengalami keruntuhan di titik akhir. Reformasi Jembrana tidak bisa juga dilihat sebagai audacious reform yang penuh. Bupati IGW memang bertindak secara berani dan nekat menggunakan kekuasaan dan otoritasnya untuk melancarkan reformasi secara cepat. Namun drama reformasi Jembrana tidak hanya mengisahkan tentang keberanian dan kenekatan Bupati IGW dalam memperjuangkan reformasi, maupun pertarungan beragam aktor dalam mengkontestasikan reformasi. Jembrana tidak hanya menyajikan drama reformasi, tetapi drama besar yang melibatkan pertarungan kekuasaan dan reformasi, yang membuahkan kejayaan dan keruntuhan ganda (kekuasaan dan reformasi) Bupati IGW. Drama reformasi Jembrana lebih tepat dipahami dengan model contentious reform. Model ini bukan hanya mampu memahami tentang interplay antara 56 kekuasaan dan reformasi, tetapi juga menunjukkan pertarungan secara episodik, dramatis dan dinamik, yang membuahkan cerita sukses reformasi dan kejayaan kekuasaan secara temporer, yang berakhir dengan kegagalan-keruntuhan reformasi maupun kekuasaan. D.2.3. Mekanisme Contentious Reform Studi ini berupaya membangun “teori himpunan” antara agensi-konteks dengan teori contentious politics di atas untuk memahami dan menjelaskan drama contentious reform di Jembrana. Jika teori contentious politics merumuskan mekanisme pertarungan politik mengandung tiga elemen (politik, pertarungan dan aksi kolektif), maka “teori himpunan” studi ini membangun mekanisme contentious reform yang dibentuk oleh tiga elemen: konteks politik (political context), agensi politik (political agency) dan pertarungan politik (political contention), seperti tersaji dalam bahan 1.5. Bagan 1.5 Mekanisme contentious reform Contentious Reform Pertarungan Politik Konteks Politik Agensi politik 57 Pertama, konteks politik (political context), yang mencakup kultur politik, struktur birokrasi, komposisi partai dan parlemen lokal, formasi elite, regulasi nasional, maupun institusi informal. Konteks bukan bermakna sebagai variabel pendahulu yang mempengaruhi variabel bebas dan kemudian berpengaruh terhadap variabel terikat; konteks bukan juga sebagai variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat. Konteks sebenarnya merupakan konsep kenyal, yang bisa dimengerti sebagai kesempatan politik yang memberikan peluang bagi tindakan aktor, atau lingkungan politik yang melatari tindakan pertarungan politik dan prakarsa reformasi. Jika dikaitkan dengan pengertian politik (siapa memperoleh apa, bagimana dan kapan), konteks sebenarnya berkaitan dengan pertanyaan kapan, atau lebih tepatnya berkaitan dengan pertanyaan bilamana atau dalam kondisi apa. Bilamana dan dalam kondisi apa Bupati IGW melakukan tindakan reformasi? Apakah prakarsa reformasi Bupati IGW hadir dalam kondisi politik harmoni atau dalam kondisi penuh pertarungan? Ini merupakan pertanyaan yang terkait dengan konteks. Kedua, aktor dan tindakan politik (political agency) yang mencakup tindakan IGW sebagai aktor utama maupun aktor-aktor pendukung maupun aktoraktor yang menentang kekuasaan IGW dan menentang reformasi. IGW tentu merupakan aktor pemimpin-penguasa yang menggunakan kekuasaan untuk menjalankan reformasi, sekaligus mempunyai hasrat kekuasaan ketika memulai reformasi. Ia memiliki barisan pendukung kekuasaan dan reformasi baik di kalangan birokrasi maupun di luar institusi pemerintah. Ia juga mempunyai strategi untuk memenangkan reformasi dan kekuasaan sehingga meraih kejayaan meskipun berakhir dengan keruntuhan. Ketiga, proses pertarungan politik (political contention), yang di dalamnya terjadi pertarungan ide, klaim kepentingan dan wacana dalam proses konsolodasi kekuasaan dan agenda reformasi antara IGW, pendukung dan penentang. Baik political context maupun political agency tidak berdiri sendiri membentuk dan mempengaruhi cerita sukses atau cerita gagal reformasi 58 Jembrana. Keduanya saling berhubungan dan mempengaruhi (interplay). Berbeda dengan cara pandang strukturalis, political context bukanlah faktor-faktor yang menentukan cerita sukses reformasi Jembrana, tetapi sebagai kondisi yang membentuk karakteristik, motivasi, strategi dan tindakan aktor (political agency). Political agency, terutama IGW, tidak mungkin berdiri sendiri sebagai kekuatan yang menghasilkan reformasi dan membangun kekuasaan, tetapi juga dibentuk oleh political context baik yang bersifat statis dan obyektif maupun dinamissubyektif yang menjadi the bases of legacy kekuasaan IGW. Political contention menjadi arena (ranah) pertemuan antara political context dan political agency, yang membentuk contentious reform, dimana aktor-aktor terus bertarung dalam memperebutkan kekuasaan dan melancarkan reformasi, yang berlangsung secara episodik, dinamis dan dramatis. E. Metode Penelitian Studi ini bekerja dengan analisis politik kontekstual sebagai jalan tengah antara tradisi positivisme dan postmodernisme. Dihadapkan pada tradisi positivisme yang bersifat nomotetik dan mengutamakan parsimoni, analisis kontekstual berargumen bahwa perhatian terhadap konteks tidak mengacaukan deskripsi dan penjelasan tentang proses politik. Namun, sebaliknya, analisis kontekstual memromosikan pengetahuan sistematis. Terhadap versi postmodernisme yang mengutamakan kompleksitas, analisis politik kontekstual berpendapat bahwa efek konteks dan kontekstual mengedepankan deskripsi secara sistematis dan penjelasan (eksplanasi) yang memadai, sehingga memfasilitasi penemuan keteraturan proses politik (Charles Tilly dan Robert Goodin, 2006). Analisis kontekstual bukanlah sebuah studi kasus yang melakukan verifikasi teori secara deduktif, bukan juga sebagai etnografi yang melakukan eksplorasi dan interprestasi secara induktif. Analisis kontekstual merupakan jalan tengah antara dua ekstrem itu. Berbeda dengan ekplanasi konvensional (berbasis 59 variabel) dalam logika deduktif maupun interprestasi dalam logika induktif, studi ini menawarkan logika reflektif yang mendialogkan antara narasi besar dan narasi kecil dengan menggunakan interprestasi dan eksplanasi berbasis mekanisme. Teori contentious reform merupakan hasil rekonstruksi dari narasi besar (teori contentious politics dan model reformasi) dan narasi kecil (pengalaman pergulatan kekuasaan dan reformasi di Jembrana). Dengan kalimat lain studi kontekstual atas Jembrana juga memberi sumbangan terhadap modifikasi, revisi dan pengembangan teori contentious politics. Sebagai analisis kontekstual, studi ini membutuhkan kedalaman data dibanding dengan studi deduktif, meskipun tingkat kedalaman studi ini tidak sebanding dengan studi sejarah dan etnografi. Sebelum ke lapangan penulis memanfaatkan berbagai dokumen baik buku yang dipublikasikan oleh Tim Bupati IGW maupun laporan penelitian berbagai lembaga tentang Jembrana. Dalam studi lapangan mulai dari Oktober 2009 hingga Mei 2011, penulis melakukan dan menerapkan tiga metode. Pertama, diskusi terbatas secara terfokus (focus groups discussion – FGD). FGD ini merupakan metode pengumpulan data paling awal yang penulis tempuh sebelum menempuh metode lain. Dengan difasilitasi oleh DS Putra, pada akhir Oktober 2009, penulis melakukan melakukan FPD dengan sejumlah 12 orang dari komunitas Jembrana Forum. Mereka terdiri dari kaum intelektual, tokoh agama, budayawan, dan wartawan, yang penulis sebut sebagai kelompok kritis-rasional, karena melihat Jembrana dan Bupati IGW secara obyektif, jernih dan kritis. Dari FGD ini penulis memperoleh gambaran besar (big picture) tentang sejumlah hal: perjalanan reformasi Jembrana, perjalanan Bupati IGW termasuk jalan yang ditempuh sang Bupati dalam membangun kekuasaan dan melancarkan reformasi, kisah sukses reformasi hingga tanda-tanda krisis reformasi. Dari FGD ini penulis juga memperoleh petunjuk tentang peta aktor, baik pendukung maupun penentang Bupati IGW. 60 FGD lanjutkan penulis selenggarakan pada bulan Agustus 2010 dan bulan Januari 2011. FGD bulan Agustus, di saat krisis reformasi Jembrana, penulis lakukan dengan para aktivis LSM yang menentang Bupati IGW dan melancarkan gerakan antikorupsi. FGD bulan Januari 2011 penulis lakukan kembali dengan Jembrana Forum yang mendiskusikan dan menganalisis tentang krisis reformasi dan keruntuhan Bupati IGW. Kedua, wawancara mendalam dengan Bupati IGW beserta aktor-aktor pendukungnya dan aktor-aktor penentangnya. Wawancara pertama penulis dengan Bupati IGW akhir Oktober 2009 memperoleh gambaran yang memadai tentang konsep dan visi reformasi serta strategi kekuasaan Bupati IGW dalam melancarkan kekuasaan. Tentu informasi sisi gelap sang Bupati tidak penulis peroleh dari IGW melainkan dari sumber-sumber lain baik dari kawan dekat maupun para penentangnya. Sejumlah kawan dekat Bupati IGW memberikan informasi yang lengkap tentang perjalanan IGW mulai dari asal-usul, sampai dengan IGW meraih kekuasaan pada tahun 1998-2000 dan menderita kekalahan pada tahun 2010. Informasi serupa juga penulis peroleh dari para penentang abadi Bupati IGW maupun para pendukungnya pada tahun-tahun awal yang kemudian berubah menjadi penentangnya pada tahun-tahun akhir karena kekecewaan. Ketiga, dokumentasi, yakni mengumpulkan berbagai data dokumen baik dokumen resmi yang dipublikasikan oleh Kabupaten Jembrana maupun berita dari berbagai koran. Para wartawan Nusa, Bali Post, Radar Jembrana dan Antara memberikan informasi yang memadai tentang Jembrana khususnya sejak tahun 2005. Untuk memperoleh informasi Jembrana sebelum 2005 penulis melacak ke kantor Bali Post maupun Perpustakaan Daerah Jembrana, tetapi hasilnya nihil. Penulis memperoleh data Jembrana dan Bupati IGW dari koran secara lengkap di Perpustakaan Daerah Provinsi Bali. Bersamaan dengan pengumpulan data penulis juga melakukan analisis data. Mengorganisir, memilah, memilih dan melengkapi data merupakan pekerjaan konvensional yang penulis lakukan. Penulis menggunakan metode triangulasi 61 antara data dokumen, data FGD maupun data wawancara untuk keperluan membangun validitas data, sekaligus melakukan konfirmasi (cross check) antara satu sumber dengan sumber lain dengan wawancara. Melampaui tugas penyiapan data ini, langkah penting pertama penulis adalah merekonstruksi narasi drama reformasi, mulai perebutan kekuasaan pada tahun 1998-2000 hingga keruntuhan reformasi dan kekuasaan pada akhir tahun 2010. Langkah kedua adalah penyusunan episode (babak) drama reformasi Jembrana yang berbentuk spiral, yakni mulai dari gerakan reformasi dan perebutan kekuasaan (1998-2000), inisiasi reformasi dan konsolidasi kekuasaan (2001-2003), kejayaan reformasi dan dominasi kekuasaan (2003-2008) hingga krisis reformasi dan keruntuhan kekuasaan (2008-2010). Langkah ketiga adalah memberikan interpretasi dan ekplanasi setiap babak drama reformasi dengan cara menunjukkan pemetaan dan narasi terhadap mekanisme interaksi antara political agency (aktor-aktor beserta sikap dan tindakan mereka), political contention (pertarungan politik antaraktor) serta political context (situasi dan kesempatan yang membentuk tindakan dan pertarungan politik antaraktor). Langkah keempat adalah menarik abstraksi dan kesimpulan untuk membangun teori serta menyajikan pembelajaran berharga tentang reformasi dan pergulatan kekuasaan. F. Alur dan Sistematika Narasi karya ini disajikan ibarat sebuah panggung drama (repertoire) yang berlangsung secara episodik dan tematik ke dalam depalan bab. Setiap penonton drama biasanya berharap dan sangat senang kalau alur cerita berakhir dengan kemenangan dan kebahagiaan (happy ending), dan sangat sedih jika sang pelaku utama akhirnya menderita kekalahan. Karya ini tidak menyajikan sebuah drama yang lumrah, drama yang berakhir dengan happy ending, melainkan drama yang berakhir dengan tragedi yang menyedihkan (sad ending). Menyusul paparan di Bab I yang telah memberikan pengantar konseptualisasi, Bab II memberikan latar konteks, sebagai tempat (place) dan 62 ruang (space), bagi arena pergulatan kekuasaan dan reformasi di Jembrana. Cerita terpenting dalam bab ini adalah arus reformasi nasional 1998 yang berdampak signifikan terhadap struktur dan institusi politik di Jembrana. Reformasi telah meruntuhkan dominasi ABG (ABRI, Birokrasi dan Golkar) dan dominasi kasta tinggi (brahmana dan ksatria); menghadirkan PDIP sebagai partai dominan baru sejak 1999 yang menjadi arena baru bagi aktor-aktor baru termasuk yang berasal dari kasta rendah (weisa dan sudra); serta perubahan politik Islam yang lebih cair dan kompetitif. Bab III bercerita tentang babak pertama, yakni perlawanan terhadap penguasa dan perebutan kekuasaan, yang terdiri dari dua babak sekaligus. Babak pertama, tahun 1998 hingga 2000, bercerita tentang aksi IGW di luar pagar kekuasaan yang membawa reformasi untuk menentang penguasa, dan secara gemilang meraih kemenangan dalam perebutan kekuasaan melalui Pilkada 2000. IGW memenangkan Pilkada Jembrana pada bulan Juli 2000, tetapi ia gagal dilantik pada 15 Agustus 2000 karena dilawan dan digagalkan oleh aksi massa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Setelah melewati jeda selama tiga bulan, IGW dilantik secara aman dan resmi pada tanggal 15 November 2000. Bab IV merupakan narasi babak kedua, 2000 hingga 2003, menceritakan tentang konsolidasi kekuasaan dan inisiasi reformasi. Pasca pelantikan Bupati 15 November 2000, IGW merasa memiliki kekuasaan yang sangat powerful di hadapan birokrasi tetapi ia merasa sangat lemah (powerless) di hadapan DPRD dan partai politik terutama PDIP sebagai partai dominan. Resistensi Fraksi PDIP dan perlawanan reaksioner dari elite dan massa PDIP masih tetap berlanjut, yang cukup menggoncang legitimasi IGW. Dalam konteks ini IGW melancarkan reformasi dan konsolidasi kekuasaan yang berhasil meredam resistensi dan berujung pada penguatan kekuasaan setelah berhasil merebut PDIP tahun 2003. Bab V bercerita tentang babak ketiga, 2003-2008, episode kejayaan reformasi dan dominasi kekuasaan. Keberhasilan IGW merebut PDIP tahun 2003 menjadi puncak konsolidasi kekuaaan, dan awal dominasi kekuasaan. Konsolidasi 63 kekuasaan dan inisiasi reformasi pada baba kedua yang berhasil itu membuahkan hasil ganda: dominasi kekuasaan dan sukses reformasi. IGW kian mempertahankan dan mengwetkan kekuasaan pada pilkada 2005. Pada saat yang sama ia melanjutkan reformasi. Namun di balik ini IGW mulai mencari keuntungan ekonomi dan akumulasi kekayaan sebagai modal untuk bertarung menjadi gubernur bali 2008. Bab VI adalah babak keempat, 2008-2011, yang menampilkan cerita tentang krisis, kemesorotan, kegagalan dan keruntuhan reformasi dan kekuasaan bupati IGW. Pecah kongsi antara IGW dengan PDIP serta kekalahan IGW dalam pemilihan gubernur Bali pada pertengahan 2008 menjadi titik puncak kekayaan, dan titik awal keruntuhan. PDIP sebagai partai dominan terus melawan IGW. BPK juga terus menunjukkan penyimpangan dan ketidakberesan keuangan Jembrana. Lawan-lawan politik di masyarakat melawan IGW dengan gerakan antikorupasi sejak 2009. Warisan reformasi, seperti Jaminan Kesehatan Jembrana, mengalami krisis dan kebangkutan. Tahun 2010 pertarungan menjadi kompleks dan dramatis. Semua aktor bertarung melawan IGW sehingga IGW jatuh dan gagal membangun dinasti politik pada pilkada 2010. Pada saat yang sama ia diseret menjadi tersangka korupsi, yang pada bulan Januari 2011, ia dimasukkan ke penjara. Bab VII mengatakan bahwa rangkaian narasi reformasi Jembrana merupakan contentious reform secara episodik dan spiral yang berakhir secara tragis. Contentious reform dibentuk oleh contentious politics. Penulis merangkum dan merajut rangkaian empat babak drama reformasi Jembrana, sekaligus menarik abstraksi dengan menggunakan kerangka konseptual tentang contentious reform. Tentu bab VII itu berguna untuk mengantarkan abstraksi teori pada bab VIII. Agenda terpenting dalam bab terakhir ini adalah membangun konstruksi teori contentious reform dengan memperhatikan dimensi aktor, konteks dan pertarungan. Di bagian akhir bab VII ini penulis menampilkan tema “Melampaui Jembrana” sebagai narasi yang menarik pembelajaran serta mengkaji ulang atau menantang teori-teori reformasi dan teori-teori kekuasaan elite, bahkan 64 mengajukan revisi atas teori contentious politics. Dengan kalimat lain, bagian ini menampilkan sisi novelty model contentious reform bila disandingkan dengan teori-teori sebelumnya, sekaligus menyajikan sisi kontribusi contentious reform bagi studi politik. 65