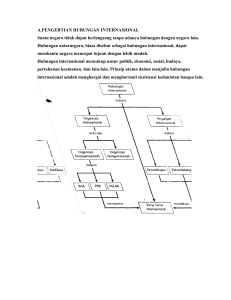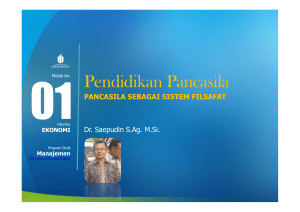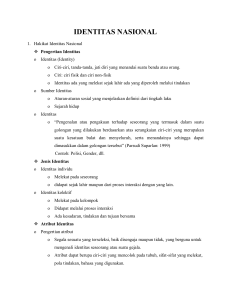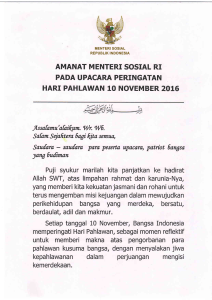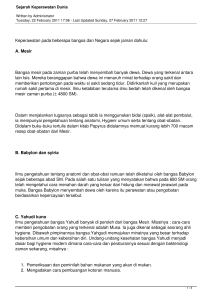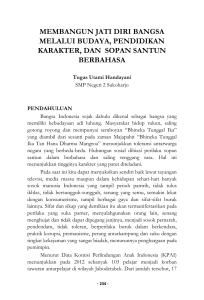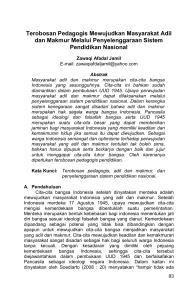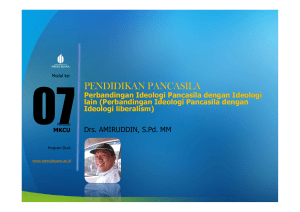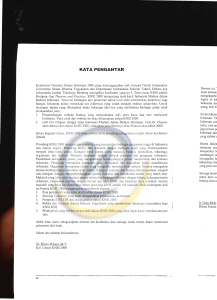Warisan Nilai Luhur - UPT Pusat Pengkajian Pancasila
advertisement

Memperkuat Social Paedagogy untuk Merajut Persatuan dan Kesatuan Bangsa1 Prof. Dr. Supriyono, M.Pd. Warisan Nilai Luhur Bangsa Indonesia memiliki pohon keluhuran yang menjulang tinggi dengan akar yang terhunjam kuat dalam perut bumi Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Pohon keluhuran dimaksud terkristalisasi dalam falsafah hidup atau pandangan hidup (way of life) Bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Itulah identitas dan sekaligus karakter yang seharusnya melekat dalam diri bangsa ini, apakah di tingkat individu warga bangsa ataukah di tingkat kolektivitas. Oleh sebab itu, adalah suatu keharusan bagi bangsa ini untuk melestarikan keluhuran tersebut sampai kapan pun sehingga Bangsa Indonesia tetap terjaga keluhurannnya dari generasi ke generasi. Keharusan untuk melestarikan karakter dan identitas bangsa yang Pancasilais tersebut tentu saja perlu dilakukan secara sadar, sengaja dan terencana. Hal itulah yang perlu diupayakan dan ditunaikan oleh Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia. Karenanya, dalam UU RI tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara tegas dinyatakan bahwa ”Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama dan kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman” (Ketentuan Umum, pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional). Konseptualisasi ”pendidikan nasional” sebagaimana disebutkan di atas mengandung implikasi yang sangat jelas, yaitu: Pertama, keharusan Sistem Pendidikan Nasional untuk melestarikan identitas dan karakter bangsa yang Pancasilais. Kedua, keharusan Sistem Pendidikan Nasional untuk tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Ketiga, keharusan yang disebutkan pertama dan keharusan yang disebutkan kedua bukanlah untuk dipertentangkan satu sama lain, melainkan untuk ”dipersandingkan” sehingga senantiasa tercipta perubahan dan kesinambungan (change and continuity); menjadi bangsa yang senantiasa tumbuh dan berkembang ke arah yang semakin maju dan sejahtera dengan tetap terpelihara identitas dan karakter ke-Indonesiaannya yang Pancasilais. Ketiga implikasi tersebut perlu diupayakan secara sadar, sengaja dan terencana, tidak hanya pada jalur pendidikan formal, melainkan juga pada jalur pendidikan nonformal dan pendidikan informal. Selama ini, masih belum tampak dilakukan upaya pengembangan jalur 1 Disampaikan pada seminar nasional “Merajut Persatuan dan Kesatuan Bangsa dengan Bhinneka Tunggal Ika dalam Perspektif Pendidikan”, yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Pancasila Universitas Negeri Malang dalam rangka Dies Natalis ke 62, tanggal 29 Oktober 2016, berdasarkan surat Rektor UM No. 9.9.6/UN32/TU/2016 tanggal 9 September 2016. Prof. Dr. Supriyono, M.Pd. adalah Guru Besar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. pendidikan nonformal dan pendidikan informal secara sadar dan terencana di dalam Sistem Pendidikan Nasional. Dengan kata lain, ”jalur pendidikan nonformal dan informal” masih terbengkalai. Padahal, usaha sadar dan terencana pengembangan pendidikan nonformal dan informal itu sesungguhnya dapat dilakukan demi tercipta ”suguhan yang mendidik” dalam realitas kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga dan lingkungan kehidupan sosial lainnya, termasuk tempat kerja, media massa, media sosial, dan ruang publik apapun. Dengan begitu, identitas dan cita-cita bangsa yang Pancasilais menjadi sesuatu yang hadir dan ”tersuguhkan” dalam keseharian hidup indivividu, komunitas, dan Bangsa Indonesia. Intervensi ke arah itu merupakan ruang spesifik bagi pengembangan pendidikan nonfomal dan pendidikan informal dalam Sistem Pendidikan Nasional dalam sistem pendidikan nasional. Sementara itu upaya pelestarian nilai-nilai keluhuran Bangsa Indonesia secara sistemis juga dilakukan melalui jalur pendidikan formal, kesekolahan, melalui mata pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN) dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Tetapi mengapa hasil-hasil pendidikan tentang nilai-nilai keluhuran itu seperti tidak berbekas dalam kehidupan sehari-hari? Anomali Bangsa Dewasa ini berbagai pihak kerap mempertanyakan ”ada apa dengan bangsa ini?” Kenapa keadaan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedemikian banyak masalah? Mengapa krisis moral berlangsung sedemikian parah? Mengapa rasa persatuan-kesatuan dari bangsa ini seakan-akan sirna? Mengapa korupsi menggurita di mana-mana? Mengapa kesantunan dan rasa kebersamaan seakan-akan hilang dalam sikap dan perilaku bangsa ini? Pendek kata ”mengapa pohon keluhuran yang menjulang tinggi dan berakar kuat di sanubari bangsa ini seakan-akan menghilang? Ada apa? Mengapa bisa demikian?” Benarkah ini dampak euphoria reformasi? Tetapi mengapa jadi berlarut-larut? Munculnya euphoria politik sebagai dialektika runtuhnya rezim Orde Baru, berupa keinginan menjadi bangsa yang demokratis, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), menghargai dan taat hukum merupakan beberapa karakter bangsa yang diinginkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun, kenyataan yang ada justru menunjukkan fenomena yang sebaliknya. Konflik horizontal dan vertikal yang ditandai dengan kekerasan dan kerusuhan muncul di mana-mana, diiringi mengentalnya semangat kedaerahan dan primordialisme yang bisa mengancam integrasi bangsa; praktik korupsi, kolusi dan nepotisme tidak semakin surut malahan semakin berkembang; demokrasi penuh etika yang didambakan berubah menjadi demokrasi yang kebablasan dan menjurus pada anarkisme dan manipulasi suara rakyat menjadi kendaraan kepentingan elite; kesantunan sosial dan politik semakin memudar pada berbagai tataran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; kecerdasan kehidupan bangsa yang dimanatkan para pendiri negara semain tidak tampak, semuanya itu menunjukkan lunturnya nilai-nilai luhur bangsa. Di kalangan pelajar dan mahasiswa dekadensi moral ini tidak kalah memprihatinkan. Perilaku menabrak etika, moral dan hukum dari yang ringan sampai yang berat masih kerap diperlihatkan oleh pelajar dan mahasiswa. Kebiasaan mencontek pada saat ulangan atau ujian masih dilakukan. Keinginan lulus dengan cara mudah dan tanpa kerja keras pada saat ujian nasional menyebabkan mereka berusaha mencari jawaban dengan cara tidak beretika. Mereka mencari bocoran jawaban dari berbagai sumber yang tidak jelas. Apalagi jika keinginan lulus dengan mudah ini bersifat institusional karena direkayasa atau dikondisikan oleh pimpinan sekolah dan guru secara sistemik. Pada mereka yang tidak lulus, ada di antaranya yang melakukan tindakan nekat dengan menyakiti diri atau bahkan bunuh diri. Perilaku tidak beretika juga ditunjukkan oleh mahasiswa. Plagiarisme atau penjiplakan karya ilmiah di kalangan mahasiswa juga masih bersifat massif. Bahkan ada yang dilakukan oleh mahasiswa program doktor. Semuanya ini menunjukkan kerapuhan karakter di kalangan pelajar dan mahasiswa. Hal lain yang menggejala di kalangan pelajar dan mahasiswa berbentuk kenakalan. Beberapa di antaranya adalah tawuran antar pelajar dan antar mahasiswa. Di beberapa kota besar tawuran pelajar menjadi tradisi dan membentuk pola yang tetap, sehingga di antara mereka membentuk musuh bebuyutan yang diwariskan dari angkatan ke angkatan. Tawuran juga kerap dilakukan oleh para mahasiswa seperti yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa pada perguruan tinggi tertentu di kota-kota besar maupun kota kecil. Bentuk kenakalan lain yang dilakukan pelajar dan mahasiswa adalah meminum minuman keras, pergaulan bebas, dan penyalahgunaan narkoba yang bisa mengakibatkan depresi bahkan terkena HIV/AIDS. Fenomena lain yang mencorong citra pelajar adalah dan lembaga pendidikan adalah maraknya “gang pelajar” dan “gang motor”. Perilaku mereka bahkan seringkali menjurus pada tindak kekerasan (bullying) yang meresahkan masyarakat dan bahkan tindakan kriminal seperti pemalakan, penganiayaan, bahkan pembunuhan. Semua perilaku negatif di kalangan pelajar dan mahasiswa tersebut atas, jelas menunjukkan kerapuhan karakter yang cukup parah yang salah satunya disebabkan oleh tidak optimalnya pengembangan karakter di lembaga pendidikan di samping karena kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Sebagai bangsa yang memiliki keragaman dalam pelbagai aspek, konflik sosial merupakan fenomena yang tidak mungkin bisa dihindarkan. Di beberapa kajian teoritik seperti dalam antropologi dan sosiologi, keragamaan yang dimiliki suatu bangsa, sebagaimana yang juga dimiliki oleh bangsa Indonesia, selalu dipandang sebagai suatu kekuatan sosial yang memiliki potensi positif. Keragaman yang tercermin pada identitas kolektif suatu kelompok sosial, dapat menciptakan ikatan kohesif yang dapat memperkuat posisi tawar dengan kelompok sosial lainnya. Tidak salah bila para pendiri Republik ini memilih semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” sebagai gambaran keberagaman dan persatuan bangsa Indonesia. Tetapi, di sisi lain, sebagaimana ditunjukkan oleh sejumlah penelitian, keragaman tersebut berpotensi juga dalam menciptakan stereotip dan kecurigaan terhadap kelompok lain. Maka bisa dipastikan, sikap tersebut menjadi pintu masuk munculnya konflik sosial (Warnaen, 2002; Sihbudi dan Nurhasim, ed., 2001). Pluralisme di Indonesia sudah ada sejak dulu, mulai dari keberagaman etnis, budaya, adat istiadat, bahasa, mata pencaharian, sampai keberagaman agama. Pluralisme di Indonesia pernah terancam oleh pemaksaan penyeragaman. Namun penyeragaman tersebut tidak mampu berhasil menghapus pluralisme. Menanamkan pluralisme dan toleransi penting dilakukan di Indonesia untuk mengelola keberagaman tersebut sehingga tidak berkembang menjadi konflik, perpecahan, dan kehancuran. Dunia pendidikan berperan besar dalam mengajarkan dan mendidik nilai-nila pluralisme di Indonesia, sejak dari tingkat pendidikan usia dini sampai pendidikan tinggi, melalui jalur pendidikan formal, nonformal, maupun informal. Namun demikian perlu disepakati tidak perlu ada mata pelajaran khusus tentang pendidikan kebhinnekaan (multi cultural), pendidikan pluralisme, atau pendidikan keberagaman dan persatuan, atau pun pendidikan perdamaian. Pemahaman dan aktualisasi keberagaman dan persatuan (diversity and unity) lebih baik diajarkan melalui kurikulum tersembunyi (hidden curriculum) dan pendidikan secara nonformal dan informal. Dalam khasanah kebijakan Mendikbud (2016) sekarang dikemas sebagai Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang tengah dimulai proyek pilotnya di sekolah-sekolah. Wawasan budaya monolitik, dapat menggrogoti integrasi bangsa serta pada saat yang sama, juga secara progresif berdampak menggerus modal sosial bangsa, yang justru sangat diperlukan dalam rangka pemulihan perekonomian nasional, yaitu keberagaman. Berdasarkan tesis ini pemeliharaan dan pengembangan keragaman budaya perlu dilakukan. Sebaliknya pengembangan budaya monolitik, penyeragaman, dan intoleran terhadap perbedaan dan keberagaman perlu dicegah, apalagi bila penyeragaman dilakukan dengan cara pemaksaan, tekanan, dan teror. K.H Hasyim Muzadi (2008) ketika menjadi panelis dalam Seminar Nasional dan Diskusi Panel Pendidikan Damai di Universitas Negeri Malang menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang masing-masing berpotensi damai tetapi juga dapat berpotensi konflik. Faktor-faktor tersebut adalah agama, etnis, budaya, dan kepentingan. Faktor agama berperan penting dalam pendidikan damai. Konflik berlatar agama terjadi karena belum ada keseimbangan antara agama sebagai nilai kognitip dan nilai universal. Ketika keduanya tidak seimbang, akan muncul eksklusivitas agama. Diluar islam atau kristen nilai-nilai itu sama, misalnya bahwa orang berbuat baik pasti dapat pahala. Etnis dan budaya juga berpotensi sebagai pemecah perdamaian, tetapi sekaligus mampu menjadi pemicu konflik. Oleh karena itu harus ada landasan moral dan agama dalam memandang berbagai keragaman etnis dan budaya. Sebagai contoh, dalam Islam tidak ada perbedaan bangsa dan etnis, semua bangsa dan etnis memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah dan dalam menjalankan agama. Dalam konteks ini K.H. Hazim Muzadi (2008) berpendapat ada kesalahan pandangan di masyarakat bahwa bangsa Arab merupakan bangsa yang paling islami. Akibatnya, setiap budaya yang berbau Arab dipandang islami: musikmusik Arab adalah musik yang islami (padahal tidak semuanya benar), pakaian Arab merupakan pakaian yang paling islami, dan sebagainya. Di sisi lain, orang Indonesia juga memiliki persepsi bahwa segala yang berbau barat (dinyatakan dalam istilah-istilah dalam bahasa Inggris) dikesani sebagai lebih ilmiah. Orang sering menggunakan bahasa Inggris biar dikira pandai tetapi belum tentu pintar. Ini contoh bahwa kita masih menempatkan bangsa tertentu sebagai lebih tinggi dari lainnya. Konflik yang paling berat adalah konflik antar kepentingan. Pengendalian konflik tidak cukup dengan edukasi, terkadang juga diperlukan represi. Dulu, pada jaman pemerintahan Orde Baru, konflik antarkepentingan tidak tampak karena tindakan represif pemerintah. Pada era reformasi, saat bangsa Indonesia merasa keluar dari kungkungan, kebebasan kita meledak sampai tak terukur porsinya. Ledakan tersebut ditunjang oleh konflik Timur Tengah yang dibawa ke Indonesia sehingga peristiwa di Bali (bom Bali, pen.) dikesani sebagai perilaku Islam Indonesia. Padahal bukan seperti itu. Konflik antarumat beragama perlu dipecahkan bersama oleh pemuka-pemuka agama. Lebih lanjut, konflik dengan alasan agama, etnis, budaya, dan antarkepentingan harus diselesaikan bersama-sama antar berbagai pihak melalui kesadaran kebhinenaan dan ke-eka-an dalam berbangsa dan bernegara. Masalah muncul ketika keberagamaan individu yang telah berkembang menjadi identitas kelompok berhadapan dengan identitas kelompok lainnya, karena sebagaimana dikatakan Johnstone (1983): “Group members feel and express a sense of identification with the group”. Dalam kajian antropologi dikenal konsep bounded system untuk menggambarkan adanya teritorialisasi masyarakat berdasarkan wilayah geografis dan nilai-nilai kebudayaannya (Abdullah, 1999). Masyarakat memiliki kecenderungan alami mempertahankan batas-batas terioterialnya tersebut, sebagaimana yang juga terjadi dalam kehidupan agama. Dalam konteks ini, selalu terjadi paradoks antara in-group dan out-group yang mengambil beberapa bentuk sebagai berikut: pertama, stereotip, yakni pandangan (image) umum suatu kelompok tentang kelompok lainnya. Meskipun stereotip ada yang berkonotasi positip, tetapi pada umumnya stereotip selalu digunakan untuk memberikan pencitraan negatif terhadap kelompok lain. Terhadap kelompoknya sendiri selalu diberi penilaian sebagai kelompok terpandai dan superior (as virtuos and superior), yang melahirkan sikap: willingness to fight and die for in- group. Sedangkan terhadap kelompok luar dipandang sebaliknya, yaitu rendah, immoral, dan inferior ( as contemtible, immoral, and inferior), yang melahirkan sikap: distrust and fear of the out-group (Levine dan Campbell, 1972). Dalam kehidupan antar umat beragama stereotip juga mudah terjadi sebagai konsekuensi dari adanya dimensi kemutlakan dalam agama, terutama yang berkaitan dengan sumber, konsep keselamatan, dan kehidupan eskatologis. Tidak ada agama di dunia ini yang tidak membicarakan hal tersebut. Hanya yang menjadi persoalan adalah ketika kemutlakan tersebut memunculkan klaim kebenaran (truth claim) yang kemudian menegasikan kebenaran lainnya. Ini jelas bagian dari stereotip karena terdapat pencitraan (image) negatif terhadap kebenaran agama lain. Bila praktik agama mengarah pada sikap mau benarnya sendiri (truth claim) yang menegasikan terhadap kebenaran lainnya, maka sikap yang demikian, dalam pandangan Kimball (2002), sama halnya dengan melakukan pembusukan terhadap agama. Potensi kebersamaan, keindahan, dan konflik juga terjadi karena keberagaman kebudayaan. Analisis kebudayaan perlu pula dilakukan dalam memahami konflik dan kekerasan. Kebudayaan memiliki pengaruh kuat terhadap perilaku manusia seperti perilaku dalam berhubungan dengan kelompok agama lain. Salah satu pandangan mengatakan bahwa kebudayaan manusia terdiri dari nilai, kepercayaan, norma, rasionalisasi, simbol, dan ideologi (Thompson, Ellis, dan Wildavsky, 1990). Semua unsur kebudayaan ini selanjutnya menjadi faktor determinan terhadap cara berfikir, perasaan, dan tindakan manusia ketika berinteraksi dengan lingkungan sosialnya (Gollnick dan Chinn, 2002). Namun tetap diakui adanya dialektika antara faktor subyektif manusia dengan lingkungan sosialnya. Jika dikatakan bahwa tindakan manusia dipengaruhi oleh dunia maknanya yang berbentuk kebudayaan, tidak boleh dilupakan, kebudayaan manusia sendiri sebenarnya merupakan hasil internalisasi dari lingkungan sosialnya. Ruang Social Paedagogy Bagaimana faktor kebudayaan berpengaruh terhadap konflik dan aksi kekerasan dalam kehidupan masyarakat? Telah dikemukakan bahwa dalam kebudayaan terdapat nilai, norma, simbol, rasionalisasi, dan ideologi, yang berpengaruh dalam tindakan manusia. Semua unsur kebudayaan ini tidak diperoleh manusia secara genetik, atau transmisi secara biologis, tetapi melalui proses belajar (Freedman, et.all, 1952; Ihromi, 1990). Sebagaimana halnya mekanisme biologis pada makhluk hidup yang digerakkan oleh kebutuhan, manusia juga demikian. Semua makhluk hidup butuh makanan. Jika makhluk hidup merasa lapar, secara butuh ingin makan. Kebutuhan terhadap makanan bukan kebudayaan, karena bersifat instingtif. Konsep kebudayaan baru bisa dipakai pada kasus makanan jika berkaitan dengan tata cara makan yang diperoleh melalui proses belajar. Sedangkan segala sesuatu yang bersifat instingtif tidak diperoleh melalui proses belajar. Nilai, norma, simbol, rasionalisasi, dan ideologi, hanya bisa menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia jika diperoleh melalui proses belajar. Salah satu proses penting untuk mempelajari pelbagai unsur budaya tersebut adalah melalui sosialisasi, yakni proses dalam mana individu mempelajari budaya masyarakatnya (Haralambos dan Holborn, 1994). Lewat proses sosialisasi, individu-individu masyarakat belajar mengetahui dan memahami tingkah pekerti-tingkah pekerti apakah yang harus dilakukan, dan tingkah pekertitingkah pekerti apa pulakah yang harus tidak dilakukan (terhadap dan berhadapan dengan orang lain) di dalam masyarakat. Melalui proses sosialisasi ini pula individu-individu belajar mengetahui dan memahami tingkah pekerti-tingkah pekerti apakah yang harus dilakukan, atau tidak dilakukan (terhadap dan sewaktu berhadapan dengan dia, atau dengan orang ketiga) dalam masyarakat. Ringkas kata, lewat sosialisasi warga masyarakat akan saling mengetahui peranan masing-masing dalam masyarakat, dan karenanya kemudian dapat bertingkah pekerti sesuai dengan peranan sosial masing-masing itu, tepat sebagaimana diharapkan oleh norma-norma sosial yang ada; dan selanjutnya mereka akan dapat saling menyerasikan serta menyesuaikan tingkah pekerti masing-masing sewaktu melakukan interaksi-interaksi sosial (Wignjosoebroto dan Suyanto, 2004). Melalui sosialisasi, individu bertindak sebagaimana yang dilakukan masyarakatnya. Proses semacam ini merupakan hal yang alami terjadi. Proses inilah yang disebut oleh Soekanto (1986) dengan identifikasi. Banyak aspek dalam kehidupan sosial yang menjadi bagian penting dalam proses identifikasi. Salah satu yang dapat disebut pada bagian ini adalah agama. Neglected Setelah P4 Pada masa Orde Baru, yaitu periode pemerintahan Presiden Soeharto keinginan untuk menjadi bangsa yang bermartabat, yang Pancasilais tidak pernah surut. Soeharto, sebagai pemimpin Orde Baru, menghendaki bangsa Indonesia senantiasa bersendikan pada nilai-nilai Pancasila dan ingin menjadikan warga negara Indonesia menjadi manusia Pancasila melalui penataran P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Salah satu nilai yang ingin diinternalisasikan adalah kebhinnekaan dan persatuan Indonesia. Secara filosofis penataran ini sejalan dengan kehendak pendiri negara, yaitu ingin menjadikan rakyat Indonesia sebagai manusia Pancasila, namun secara praksis penataran ini dilakukan dengan menggunakan caracara indoktrinasi dan tanpa keteladanan yang baik dari para penyelenggara negara sebagai prasyarat keberhasilan penataran P-4. Sehingga bisa dipahami jika pada akhirnya penataran P-4 ini mengalami kegagalan, meskipun telah diubah pendekatannya dengan menggunakan pendekatan kontekstual, metode dialog melalui Permainan Simulasi. Sejak Orde Baru runtuh upaya pendidikan nilai-nilai Pancasila seperti kehilangan orientasinya, bahkan yang di dalam jalur sekolahpun seperti tidak berdaya menghadapi gempuran informasi melalui media masa, media sosial, dan komunikasi interpersonal yang tersaji di ruang publik yang destruktif terhadap nilai-nilai kebhinnekaan dan persatuan. Lebih-lebih pendidikan yang melalui jalur pendidikan nonformal dan informal hampir tidak pernah terjadi karena penataran-penataran tentang Pancasila dan Kewarganegaraan tidak lagi diberikan kepada setiap warga negara, melainkan hanya diberikan pada aparatur pemerintah melalui diklat prajabatan dan diklat penjenjangan karir. Pengembangan pendidikan nonformal dan informal untuk internalisasi nilai-nilai Pancasila sudah saatnya ditangani sebagai bagian integral dari Sistem Pendidikan Nasional, dan tidak dibiarkan terbengkalai atau ”menjadi bagian tak terurus” seperti selama ini. Bila hal tersebut diupayakan secara sadar dan terencana niscaya berbagai ”suguhan tak mendidik di media massa dan media sosial” serta tak sejalan dengan identitas dan cita-cita luhur bangsa, yang tersaji baik di keluarga maupun di lingkungan kehidupan sosial lainnya, secara sistematis dapat dieliminir. Sehubungan dengan itu, peran strategis jalur pendidikan nonformal dan informal sudah sepatutnya mendapat perhatian serius untuk dikembangkan. Sebab, pasar bebas ide-ide yang berkembang pesat dewasa ini dapat menyebarkan ”virus liar” yang tak sejalan dengan identitas dan cita-cita luhur bangsa, dan itulah yang kental menggejala belakangan ini, khususnya bila menyimak ”suguhan” yang terpajang di media massa, media sosial, dan komunikasi publik yang berfungsi sebagai pedagogy sosial. Bila hal tersebut dibiarkan tanpa intervensi yang sifatnya edukatif niscaya berakibat buruk bagi upaya pelestarian identitas dan cita-cita luhur Bangsa Indonesia; peran jalur pendidikan formal tak akan memadai untuk menanggulanginya, disamping terlalu lama dalam menghasilkan dampak perbaikan pada khalayak sasaran peserta didik. Dengan demikian, pengembangan jalur pendidikan informal sebagai suatu usaha sadar dan terencana menjadi suatu kebutuhan dan keharusan di dalan Sistem Pendidikan Nasional, termasuk untuk Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Teori strukturasi Anthony Giddens (1984) sangat relevan digunakan untuk menjelaskan fenomena pedagogi sosial dan lunturnya penghayatan nilai-nilai Pancasila. Selaku teoritikus sosiologi paling terkemuka masa kini, Giddens berhasil mensintesiskan dua kutub teori dalam sosiologi yang selama ini berseberangan, yaitu kutub teori strukturalisme dan kutub teori interaksionisme. Kutub teori strukturalisme pada dasarnya berpandangan bahwa individu dalam suatu masyarakat adalah semacam ”hamba” yang sehari–hari dituntut tunduk kepada struktur yang menjadi tuannya. Sebab, tatanan masyrakat yang menstruktur dalam kenyataannya telah ada dan terbentuk sebelum seseorang (warga masyarakat) itu lahir sehingga warga pendatang baru tersebut tinggal menyesuaikan diri dengan tuntutan struktur yang berlaku di tempat ia berada. Sebaliknya, kutub teori interaksionisme berpandangan bahwa struktur yang menjadi tatanan masyarakat itu tidak pernah dan tidak dapat berbuat apapun; yang berbuat adalah orang atau individu. Karenanya, suatu struktur sesungguhnya merupakan produk interaksi warga masyarakat itu sendiri. Melalui interkasi warga masyarakat itulah terbangun negosiasi sehingga tercipta tatanan atau struktur yang akhirnya menuntun sikap dan perilaku mereka sehari-hari. Oleh Giddens, kedua kutub teori tadi disintesiskan atau dikawinkan menjadi satu teori sintesis, yang sekarang dikenal dengan nama Teori Strukturasi. Menurut teori strukturasi ini, struktur itu bukanlah sesuatu yang final dan statis, melainkan selalu dalam proses menjadi yang tiada akhir. Struktur dan individu warga masyarakat bersifat interaktif, yaitu sama-sama saling menentukan dan ditentukan. Struktur bersifat menentukan, yaitu menentukan perilaku individu warga masyarakat, tetapi pada waktu bersamaan juga ditentukan oleh individu (warga masyarakat). Sebaliknya, individu (warga masyarakat) ditentukan oleh struktur, tetapi pada saat bersamaan juga ikut menentukan struktur. Dalam istilah Giddens, struktur itu medium dan sekaligus outcome. Sementara itu individu (warga masyarakat) adalah reproduser (pelestari struktur) dan sekaligus juga produser (pencipta struktur). Berdasarkan teori strukturasi Giddens tersebut tampak jelas bahwa pohon keluhuran Bangsa Indonesia (sekalipun berakar kuat dalam budaya bangsa) bukanlah sesuatu yang final dan statis; bukan sesuatu yang tak tergoyahkan, melainkan senantiasa mengalami proses reproduksi dan produksi secara terus menerus tanpa akhir, bahkan bisa tergradasi. Yang melakukan reproduksi dan produksi tidak lain adalah individu warga masyarakat itu sendiri. Itu berarti, keadaan yang mengecewakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dewasa ini adalah buah dari proses reproduksi dan produksi dalam kehidupan sehari-hari. Itulah hasil belajar bangsa ini dalam lingkungan intreraksi mereka sehari-hari. Apa yang mereka serap dari media massa, lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan sehari-hari di masyarakat, organisasi, tempat kerja, permukiman, pusat layanan publik dan sebagainya ikut menjadi sumber belajar (”sekolah”) yang memproduksi realitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dewasa ini. Proses reproduksi dan produksi ”pohon keluhuran” yang menjadi identitas Bangsa Indonesia sudah seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab utama lembaga pendidikan formal, nonformal, dan informal. Sesuai dengan teori strukturasi Giddens, lembaga pendidikan tentu saja perlu secara sadar dan terencana menciptakan lingkungan kehidupan yang mendidik di manapun dan kapanpun, yaitu sejalan dengan identitas dan cita-cita luhur bangsa ini, sehingga dapat memelihara dan memupuknya. Dengan demikian, pengembangan pendidikan menjadi suatu keharusan bila tak ingin bangsa ini berkembang semakin jauh menyimpang dari nilai-nilai kepribadian luhur yang dimilikinya. Revitalisasi Gerakan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Nilai-nilai luhur ”hadiah masa lampau” dari bangsa ini patut disyukuri, dihargai dan dilestarikan dari generasi ke generasi. Keluhuran tersebut merupakan modal sosial, budaya dan spiritual Bangsa Indonesia yang tak ternilai harganya asalkan tetap tertanam dalam kesadaran masyarakat dan teraktualisasi ke dalam praktik kehidupan sehari-hari. Modal itulah yang harus dipupuk terus agar tetap tumbuh, berkembang dan membudaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hal tersebut tentu saja menjadi tugas utama dunia pendidikan, yaitu oleh Sistem Pendidikan Nasional, yang mencakup jalur pendidikan formal, nonformal dan informal. Mengapa dunia pendidikan harus memupuk modal keluhuran dimaksud secara terus menerus? Mengapa Sistem Pendidikan Nasional harus mengemban fungsi pelestarian tersebut secara berkesinambungan? Sehubungan dengan pertanyaan tersebut, menurut Fukuyama (1992) setidaknya ada dua alasan teoretis-filosofis yang dapat diajukan, yaitu: Pertama, seluhur apa pun suatu nilai, pandangan, gagasan atau keyakinan ”nasibnya” sangat bergantung pada kuat atau lemahnya pemulyaan terhadap keluhuran dimaksud oleh masyarakat. Merosotnya keluhuran suatu nilai-nilai kehidupan dalam pandangan masyarakat, merupakan gejala bahwa nilai-nilai tersebut akan pudar dan sirna dari peredaran. Hal tersebut juga bisa terjadi pada pohon keluhuran yang dimiliki Bangsa Indonesia. Hanya proses pendidikan yang dapat melestarikan nilai dan cita-cita luhur yang dimiliki Bangsa Indonesia. Kedua, suatu keluhuran apa pun hanya mungkin diwariskan atau diturunkan ke generasi berikutnya sepanjang keluhuran tersebut secara nyata masih hidup dalam keseharian masyarakat bersangkutan; yang tak lagi aktual dalam kehidupan sehari-hari tidak akan mungkin terwariskan. Hal yang demikian itu tentunya juga berlaku bagi ”pohon keluhuran” yang dimiliki bangsa ini. Karenanya, adalah tugas dunia pendidikan untuk membuatnya tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan apa pun dan dalam situasi bagaimanapun. Sejalan dengan alasan yang telah disebutkan di atas, pemikiran filsafat idealisme berkeyakinan bahwa selalu ada ide di balik segala sesuatu (things within ideas). Dan, ide ke arah kemajuan dan kehidupan lebih baiklah yang berada di balik perjalanan sejarah umat manusia dari masa ke masa, kapan pun dan di mana pun. Oleh sebab itu, bisa dimengerti bila senantiasa muncul berbagai koreksi atau perbaikan terhadap tatanan kehidupan yang menyimpang atau melenceng dari tatanan ideal yang dicita-citakan oleh suatu masyarakat/bangsa. Itulah yang dikenal dengan hukum sejarah yang sifatnya dialektikal di dalam perjalanan suatu masyarakat/bangsa menuju puncak kemajuan dan keagungan. Hal tersebut dengan jelas juga termanifestasi dalam perjalanan sejarah Negara dan Bangsa Indonesia selama ini; misalnya kekecewaan terhadap realitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di masa Orde Lama memunculkan koreksi yang melahirkan Orde Baru, dan selanjutnya kekecewaan terhadap Orde Baru dikoreksi oleh Orde Reformasi. Fenomena sejarah yang demikian itu mengisyaratkan bahwa umat manusia, termasuk Bangsa Indonesia, senantiasa memproduksi ide-ide bagi diri mereka, termasuk tentang citacita yang diidealkan untuk dicapai. Arena kehidupan dalam suatu masyarakat/bangsa tak ubahnya pasar bebas ide-ide. Akibatnya, jual beli ide-ide menjadi tak terhindar-kan. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demikian itu, fungsi pendidikan menjadi sedemikian sentral dan menentukan untuk dapat melestarikan keluhuran identitas dan karakter bangsa. Lebih-lebih di era globalisasi dewasa ini yang teknologi informasi dan komunikasinya sedemikian canggih, yang tentu saja sarat dengan dampak positif maupun negatif bagi masyarakat/bangsa ini. Sehubungan dengan itu, peran strategis pendidikan sudah sepatutnya mendapat perhatian serius untuk dikembangkan. Sebab, pasar bebas ide-ide yang berkembang pesat dewasa ini dapat menyebarkan ”virus liar” yang tak sejalan dengan identitas dan cita-cita luhur bangsa, dan itulah yang kental menggejala belakangan ini, khususnya bila menyimak ”suguhan” yang terpajan di media massa dan ruang publik, serta kounikasi interpersonal yang masif melalui media sosial. Bila hal tersebut dibiarkan tanpa intervensi yang sifatnya edukatif, niscaya berakibat buruk bagi upaya pelestarian identitas dan cita-cita luhur Bangsa Indonesia; peran jalur pendidikan sekolah tak akan memadai untuk menanggulanginya. Dengan demikian, pengembangan jalur pendidikan nonformal dan informal sebagai suatu usaha sadar dan terencana menjadi suatu kebutuhan dan keharusan di dalan Sistem Pendidikan Nasional. Penutup Indonesia adalah negara dengan keberagaman etnis, budaya, adat istiadat, bahasa, mata pencaharian, budaya, dan agama. Sebagai bangsa yang memiliki keragaman dalam pelbagai aspek, konflik sosial merupakan fenomena yang tidak mungkin bisa dihindarkan. Pluralisme di Indonesia pada satu sisi menjadi sebuah keindahan, pada sisi lain bisa menjadi ancaman bagi integrasi bangsa. Pengembangan budaya monolitik, penyeragaman, dan intoleran terhadap perbedaan dan keberagaman perlu dicegah, apalagi bila penyeragaman dilakukan dengan cara pemaksaan, tekanan, dan teror. Penyeragaman bukan merupakan solusi bagi masalah integrasi bangsa. Sikap toleransi yang terukur bisa menjadi solusi bagi terpeliharanya kebhinnekaan dan ke-eka-an Bangsa Indonesia. Dunia pendidikan berperan besar dalam mengajarkan dan mendidik nilai-nila pluralisme di Indonesia, sejak dari tingkat pendidikan usia dini sampai pendidikan tinggi, melalui jalur pendidikan formal, nonformal, maupun informal. Namun demikian perlu disepakati tidak perlu ada mata pelajaran khusus tentang pendidikan multi kultural, pendidikan pluralisme, atau pendidikan keberagaman dan persatuan, atau pun pendidikan perdamaian. Pemahaman dan aktualisasi keberagaman dan persatuan (diversity and unity) lebih baik diajarkan melalui kurikulum tersembunyi (hidden curriculum) dan pendidikan secara nonformal dan informal. Dalam khasanah kebijakan Mendikbud (2016) sekarang dikemas sebagai Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang tengah dimulai proyek pilotnya di sekolah-sekolah. Dibutuhkan adanya revitalisasi program pendidikan nonformal dan informal, termasuk pendidikan dalam keluarga yang benar-benar mampu menyelenggarkan pendidikan multikultural untuk memelihara kebhinnekaan dan ke-eka-an suatu kesatuan yang utuh, saling kompetibel, integratif, efisien, dan efektif dalam mewujudkan sosok insan kamil (manusia Indonesia seutuhnya) dan masyarakat madani (masyarakat adil dan makmur) berdasarkan Pancasila. Pustaka Abdullah, Irwan.1999. “Dari Bouded System ke Borderless Society: Krisis Metode Antropologi dalam Memahami Masyarakat Masa Kini”. Antropologi Indonesia, Tahun XXIII, No. 60, September-Desember. Freedman, Ronald, et.all. 1952. Principles of Sociology: A Text with Reading. New York : Henry Holt and Company. Fukuyama, Francis (1992), The End of History and The Last Man, London, Penguin Books. Garrick, John. 1998. Informal Learning in the Work Place, Unmasking Human Resource Development. London: Routledge Giddens, Anthony (1984), The Constitution of Society Outline of The Theory of Structuation, Berkley, University of California Press Gollnick, Donna M., Chinn, Philip C. 2002. Multicultural Education in a Pluralistic Society. New Jersey: Prentice-Hall. Haralambos, M., Holborn, M. 1994. Sociology: Themes and Perspectives. London: Collin Educational Ihromi (ed.). 1990. Pokok-pokok Antropologi Budaya. Jakarta: Gramedia Johnstone,Ronald I.1983. Religion in Society: A Sociology of Religion. New Jersey: Prientice-Hall, Inc. K.H Hasyim Muzadi. 2008. Seminar Nasional dan Diskusi Panel Pendidikan Damai di Universitas Negeri Malang, Prosiding. Malang: universitas Negeri Malang Ki Hadjar Dewantara.1938. “Sistem Trisentra”, dalam Karya Ki Hadjar Dewantara, bagian pertama, cetakan ke dua (1977), Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa. Levine, A. Robert dan Campbell, Donald T. 1972. Etnocentrism: Theories of Conflict, Ethnic Attitude and Group Behavior.New York: John Willey&Sons. Mendikbud. 2016. Penguatan Pendidikan Karakter. Dokumen tidak diterbitkan. Jakarta. Samani, Muchlas. & Hariyanto, 2013. Konsep dan Model Pendidikan Karakter. Bandung: Remaja Roedakarya. Sihbudi, Riza, et.al.2001. Kerusuhan Sosial di Indonesia: Studi Kasus Kupang, Mataram, dan Sambas. Jakarta: Grasindo Soekanto, Soerjono.1986. Sosiologi Suatu Pengantar.Jakarta: Rajawa Press Sumartana, Th. 2001. Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia. Yogyakarta: Interfidei. Thompson, Michael; Ellis, Richard; and Wildavsky, Aaron.1990. Cultural Theory: Political Cultures Series. Oxford: Westview Press. UNDANG-UNDANG Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Warnaen, Suwarsih. 2002. Stereotip Etnis dalam Masyarakat Multietnis. Yogyakarta: Mata Bangsa. Wignjosoebroto Soetantyo dan Suyanto, Bagong. 2004. Sosialisasi dan Pembentukan Kepribadian, dalam J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (ed.), Sopsiologi: Teks pengantar dan Terapan. Jakarta: Kencana.