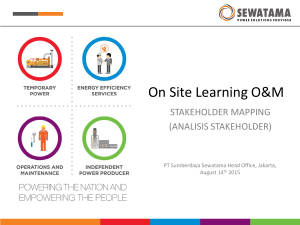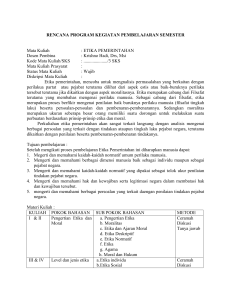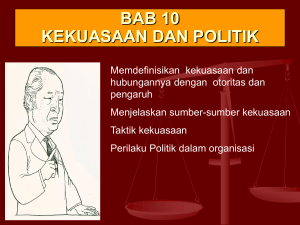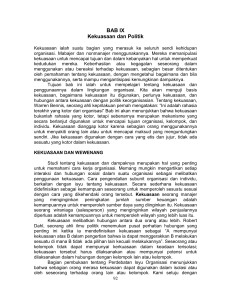FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI BASIS LEGITIMASI
advertisement

FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI BASIS LEGITIMASI DALAM PELAYANAN PUBLIK Bambang Irawan Abstract. The low quality of public services in Indonesia have long been public complaints. People often find it difficult to gain access to public services, while the public service is essentially designed and organized to meet the needs of the community. By building a good performance of public services, the government can actually build a good relationship with the community and expand its legitimacy in the public eyes. This paper attempts to strengthen the basis of legitimacy based on institutional theory and social capital. Regulatory factors, norms, culture and moral cognisi be in this study is expected to strengthen basic lagitimasi in public service. Keyword: legitimacy, regulations, norms, culture-cognisi, moral Abstrak. Rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia sudah lama menjadi keluhan masyarakat. Masyarakat sering mengalami kesulitan untuk memperoleh akses terhadap pelayanan publik, sedangkan pelayanan publik pada hakikatnya dirancang dan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan membangun kinerja pelayanan publik yang baik, sesungguhnya pemerintah bisa membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan memperluas legitimasinya di mata publik. Tulisan ini mencoba untuk memperkuat basis legitimasi berdasarkan teori institusi dan modal sosial. Faktor regulasi, norma, budaya-kognisi dan moral yang menjadi kajian dalam ini diharapkan dapat memperkuat dasar lagitimasi dalam pelayanan publik. Keyword : legitimasi, regulasi, norma, budaya-kognisi, moral Sebagaimana dipahami bahwa esensi pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu pemerintah tidak diadakan untuk dirinya sendiri tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. Pemerintah sebagai pelayan masyarakat (public service) sudah seharusnya memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Pelayanan yang berkualitas selain bermanfaat bagi masyarakat juga bermanfaat terhadap citra aparat pemerintah itu sendiri dan dengan sendirinya membentuk legitimasi terhadap pelayanan publik yang diberikan. Untuk mengembangkan pelayanan publik yang berorientasi kepada warga negara, dituntut adanya pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik. Negara dalam hal ini tidak lagi dinilai sebagai satu-satunya aktor yang berperan dalam mencapai tujuan nasional. Dalam era reformasi, sistem demokrasi menuntut adanya kekuasaan yang terdesentralisasi dimana masing-masing komponen memiliki otonomi relatif terhadap komponen yang lain, sehingga tidak ada satu elemen dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mendominasi kelompok yang lain. Munculnya aktor-aktor penting selain negara (yaitu masyarakat sipil dan sektor bisnis) dalam kehidupan sosial mengurangi dominasi peran negara sehingga negara menjadi semakin bisa diakses oleh siapa pun dengan berbagai macam kepentingannya. Konsep tersebut terkenal dengan governance, sebagai keseluruhan interaksi antara sektor public dan private dalam mencari solusi atas masalah dan peluang bagi publik. Dari perspektif governance, pemerintah dituntut untuk menunjukkan sebagai sebuah pemerintahan yang demokratis, efisien, dan memiliki sumber daya aparatur yang memiliki kehandalan akibat tekanan politik maupun tekanan kesulitan anggaran dan keuangan. Akar persoalan situasi ini terletak pada model pemerintahan yang tidak mampu beradaptasi dengan turbulensi perubahan lingkungan yang sedang terjadi. Legitimasi dapat dilihat sebagai penilaian sosial terhadap penerimaan, kesesuaian, dan atau keinginan (Zimmerman dan Zeitz, 2002). Dari perspektif governance, legitimasi dalam pelayanan publik dapat dimaknai sebagai penerimaan, kesesuaian atau keinginan masyarakat terhadap organisasi yang melaksanakan pelayanan publik. Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan adalah factor-faktor apa saja yang dapat mewujudkan legitimasi bagi organisasi? Beberapa penelitian sebelumnya menjelaskan hubungan antara teori institusi dan legitimasi organisasi (Farjoun, 2010; Pfeffer, 2005). Teori institusi dipahami sebagai struktur dan aktivitas kognisi, norma dan regulasi yang menyediakan stabilitas dan pemaknaan terhadap prilaku sosial (Scott, 1998: 133). Faktor-faktor atau elemen-elemen institusi inilah yang nantinya akan diteliti lebih jauh dalam memahami legitimasi pada organisasi pelayanan publik. Disamping itu, sebagai sebuah konstruksi sosial (Harvey and Schaefer, 2001), legitimacy tidak terlepas dari masalah moralitas. Legitimasi sebaiknya memperhitungkan moral dominand an tanggung jawab sosial dalam masyarakat di mana organisasi beroperasi meskipun nilai-nilai organisasi ada yang bertentangan dengan harapan masyarakat (Kennedy dan Fiss, 2009). Teori Institusi Kata institusi diterjemahkan dari istilah Inggris yaitu institution atau social institutions, yangsering dipadankan dengan social organizations, yaitu aspek-aspek sosial yang hidup di masyarakat dan menjadi acuan dalam berperilaku dan bermasyarakat. Walaupun tidak ada kesepakatan tunggal tentang defenisi institusi, kebanyakan ahli mengikuti kriteria North (1991: 97-112) yang membedakan antara institusi dengan organisasi. Institusi, seperti agama dan norma-norma lainnya, adalah semacam ”the rules of the game” yang terdiri dari aturan-aturan legal formal dan normanorma sosial informal yang mengatur perilaku individu dan menstruktur interaksi sosial (institutional frameworks). Organisasi, sebaliknya, adalah sekelompok orang-orang yang diciptakan untuk mengatur tindakan mengelompok mereka dalam menghadapi kelompok lainnya. Bentuk organisasi yang mudah dipahami misalnya perusahaan, sekolah, klub, asosiasi profesi dan sebagainya. Meskipun North (1991) adalah salah satu pakar yang pertama menjelaskan tentang institusi informal ini, North secara konsisten lebih menekankan institusi-institusi formal seperti konstitusi dan hukum sebagai aturan dasar atau ”the fundamental rules of the game” (1991: 97). Para ahli setelah North mengkritik terhadap konsepnya yang tidak menjelaskan mengapa individu mengikuti sebagian aturan, namun tidak mengikuti sebagian lainnya. Seperti halnya Nee (2005: 52), yang menganggap bahwa North tidak terlalu menjelaskan peranan institusi-institusi informal yang membentuk hubungan antarindividu, lalu membentuk institusi-institusi ekonomi yang unik. Menurut Nee (2005: 55), yang dimaksud dengan institusi adalah sistem dominan dari elemen-elemen yang bersifat formal dan informal seperti; kebiasaan, kesepakatankesepakatan, norma-norma,dan keyakinan yang dibagi bersama (shared beliefs), dimana para aktor mendasarkan tindakannya ketika memenuhi kepentingan masing-masing. Dari defenisi ini, Nee (2005) menggambarkan institusi sebagai struktur sosial yang menyediakan pedoman untuk melakukan tindakan bersama dengan cara memberikan aturan tentang kepentingan setiap individu dan memperkuat hubungan antara mereka, karena perilaku seseorang dipengaruhi oleh orang lain. Kerangka institusi inilah yang membentuk perilaku ekonomi masyarakat (Nee, 2005: 56). Melalui konsepsi ini, Nee (2005) memperbaiki konsep yang dirintis North (1991) yang terlalu menggunakan perspektif ekonomi dalam melihat bahwa perilaku ekonomi individu tidak dipengaruhi oleh individu lain, melainkan oleh pasar (market) dan negara (state) (Toboso, 2001: 765-784). Victor Nee (2005: 56) menjelaskan bahwa perilaku ekonomi seseorang dipengaruhioleh orang lain (actors are influenced by other actors). Konsepsi tentang perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh orang lain ini terkait dengan konsep perilaku yang berlandaskan budaya. Institusi menurut Portes (2006) adalah aturan main (rules of the game)organisasi yang merupakan satuan peraturan (formal atau informal), yang mengarahkan hubungan antara berbagai peran (roles) dalam organisasi seperti keluarga, sekolah, pemerintahan, agama dan sebagainya.Adapun struktur sosial (social structure) atau organisasi terdiri dari individu yang menjalankan peran dan terpola dalam sebuah status yang bersifat hirarkis. Antara budaya (culture) yang menekankan peranan nilai (values) dan lembaga (institutions) dengan struktur sosial (social sturcture) atau organisasi dapat dilihat sebagai evolusi hirarki pengaruh yang saling berhubungan. Norma-norma budaya adalah hal terdalam (deep) atau tebal (thick) dan struktur sosial adalah hal terluar (surface) atau tipis (thin) (Portes, 2006: 233-262). Sebahagian besar literatur hanya membandingkan perbedaan institusi (institutions) dengan organisasi (organizations). Konsep tentang defenisi keduanya sampai saat ini masih menjadi bahan perdebatan yang sengit dikalangan sarjana sosial. Di kalangan sosiolog maupun antropolog, istilah institusi sering dibingungkan dengan organisasi. Uphoff (1986) memberikan gambaran yang jelas tentang keambiguan antara institusi dan organisasi yang secara umum penggunaannya dapat dipertukarkan: “What contstitutes an ‘institution’ is asubject of continuing debate among social scientist…The term institution andorganization are commonly used interchangeably and this contributes to ambiguityand confusion”. Dengan kata lain, belum terdapat istilah yang disepakati di kalangan sarjana sosiologi tentang social institutions. Misalnya, Uphoff (1986: 9) mengatakan bahwa institusi memiliki dua bentuk, satu mengacu pada peran (roles) dan lainnya adalah struktur (structures). Beberapa sarjana mencoba untuk mengaitkan kedua konsep ini,misalnya Whitley (1996:411), sebagaimana dia katakan: ”Business systems are particular forms of economic organisation that have become established and reproduced in certain institutional contexts – local, regional, national orinternational”. Dengan kata lain bahwa sistem bisnis merupakan bentuk-bentuk organisasi ekonomi yang partikular yang telah terlembagakan dan diproduksi kembali sesuai dengan kondisi waktu dan tempat dimana bisnis itu berada. Hal ini sejalan dengan pendapat Uphoff (1986) bahwa institusi merupakan sekumpulan norma dan perilaku yang telah mentradisi dalam waktu yang lama dan digunakan untuk mencapai tujuan bersama. Institusi cenderung diartikan tradisional, sedangkan organisasi cenderung dipahami dalam konsep modern. Dari keterangan di atas, dapat dipahami bahwa institusi dan organisasi berada dalam satu rangkaian kesatuan. Organisasi merupakan bentuk struktur sosial mapan dari institusi. Organisasi dalam sebuah struktur sosial berarti di dalamnya terdapat peran dan struktur yang sudah ditetapkan tugasnya masing-masing. Orang-orang yang terlibat di dalam struktur sosial ini dapat diketahui dengan jelas sesuai dengan fungsinya dan setiap individu diikat oleh seperangkat hukum dan norma-norma sosial yang dipegang bersama, sehingga jika ada yang melanggar kesepakatan itu akan diberikan sanksi. Institusi pada dasarnya bersifat informal kemudian berkembang menjadi institusi struktur organisasi yang jelas. Begitupun dengan Nee (2005: 55-57), dalam teori institusional baru ini (new institutionalism), menjelaskan institusi sebagai sebuah sistem dominan dari elemen formal dan informal yang saling berhubungan seperti kebiasaan (customs), keyakinan yang dianut bersama (shared belief), perjanjian (conventions), norma (norms), aturan (rules), dimana aktor melandasi perbuatannya ketika memenuhi kepentingan-kepentingan mereka. Sehingga, perubahan institusi tidak hanya melibatkan pembentukan ulang aturanaturan formal tapi secara fundamental menuntut adanya pengaturan kembali (rearrangement) dari kepentingan, norma,dan kekuasaan. Dan semua proses kemunculan, resistensi, dan transformasi dari struktur institusi ini berdasarkan pada rasionalitas yang kontekstual (context-bond rationality), yaitu rasionalitas yang berdasarkan konteks masyarakat tertentu dan tertanam dalam hubungan-hubungan interpersonal. Jika konsep rasionalitas pada perspektif ekonomi klasik sepenuhnya rasional demi maksimalisasi keuntungan individu, maka rasionalitas yang sesuai konteks sosial adalah yang berlandaskan pada budaya, agama, dan kebiasaan setempat. Lewat konsep ini, Nee tidak hanya menjelaskan sosiologi ekonomi tapijuga ekonomi institusional yang baru, yang membantu kita untuk memahami lebihbaik hubungan antara individu dan kelompok yang menciptakan kegiatan-kegiatanekonomi secara bersama-sama dalam menghadapi aturan-aturan formal yang mengatur praktek ekonomi. Dengan kata lain, Nee (2005) memperkaya perdebatan antara ekonomi formalis yang pada prinsipnya tidak melekat secara sosial (social disembededdness) dengan ekonomi substantif yang melekat secara sosial (social embededdness). Selama ini, ekonomi dipahami sebagai ilmu empirik yang tergantung pada nilai-nilai yang bersifat positif dan mengabaikan nilai normatif. Padahal, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang paling bergantung pada nilai dan paling normatif diantara ilmu-ilmu sosial lainnya. Model dan teorinya akan selalu didasarkan pada sistem nilai tertentu yang terkait dengan pandangan tentang hakikat manusia dan lingkukngannya. Konsep kunci Nee (2005) menegaskan mekanisme sosial dimana aspek formal dan informal saling berhubungan dan menjadi dasar bagi setiap manusia dalam mencapai kepentingan ekonominya. Menurut Nee, aspek formal yang terdiri dari peraturanperaturan formal dari negara seperti undangundang (institutional environment) berhubungan secara dialektis dengan aspek informal seperti norma-norma dan nilai-nilai agama (shared belief), jaringan sosial (socialnetwork), kelekatan sosial (social embededdness) yang sesuai konteks sosialbudaya tertentu. Kedua aspek formal dan informal menurut Nee (2005) mempengaruhi perilaku manusia dalam melakukan kegiatankegiatan ekonominya.Teori institusional baru menelaah tentang bagaimana institusi memainkan peran yang vital dalam menstrukturisasi transaksi-transaksi sosial dan ekonomi dan memahami dasar dari norma-norma sosial, jaringan sosial dan keyakinan (sharedbeliefs) yang krusial dalam menjelaskan persoalan yang terjadi dalam praktek ekonomi modern. Adapun inti dari teori Institusional baru dirumuskan oleh seperti yang disebutkan oleh Goodin dalam Budiarjo (2008:98) meliputi aktor dan kelompok melaksanakan proyeknya dalam suatu konteks yang dibatasi secara kolektif. Pembatasan tersebut merupakan institusi-institusi, yaitu pola norma dan pola peran yang telah berkembang dalam kehidupan sosial dan perilaku dari mereka yang memegang peran itu. Adapun peran yang dimaksud telah ditentukan secara sosial dan mengalami perubahan terus-menerus, meskipun, pembatasan-pembatasan ini dalam banyak hal juga memberi keuntungan bagi individu atau kelompok dalam mengejar proyek mereka masing-masing. Hal ini disebabkan karena faktor-faktor yang membatasi kegiatan individu dan kelompok, juga mempengaruhi pembentukan preferensi dan motivasi dari aktor dan kelompok-kelompok. Pembatasan ini mempunyai akar historis, sebagai peninggalan dari tindakan dan pilihan-pilihan masa lalu dan bermaksud untuk mewujudkan, memelihara, dan memberi peluang serta kekuatan yang berbeda kepada individu dan kelompok masingmasing. Dalam berbagai teori tentang organisasi, jika prinsip-prinsip organisasi mengadopsi normanorma yang ada di lingkungannya maka organisasi menjadi terinstitusionalisasi. Proses institusionalisasi dalam organisasi dijelaskan oleh berbagai pakar sosiologi seperti Selznick (1949) yang mengatakan bahwa terdapat dua bentuk organisasi, yaitu sebagai ekspresi struktural dari tindakan rasional, sebagai instrumen mekanis yang dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, dan organisasi dianggap sebagai sebuah sistem organik yang adaptif, dipengaruhi oleh karakter-karakter sosial dari partisipasinya dan juga beragam tekanan-tekanan yang diakibatkan oleh lingkungannya. Selznick (1949) menambahkan bahwa institusionalisasi adalah sebuah proses yang akan terjadi kepada organisasi setiap waktu, yang merefleksikan sejarah organisasi, sekelompok orang-orang dengan kepentingankepentingan yang diciptakannya, dan caranya beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi, proses institusionalisasi adalah menanamkan nilai yang melampaui persyaratan teknis dari sebuah organisasi. Dengan kata lain, organisasi yang mengadaptasi nilai-nilai lingkungan (atau institusi-institusi sosial sekitar) berarti organisasi tersebut sedang melakukan institusionalisasi. Teori Modal Sosial Dalam praktek ekonomi, modal sosial amatlah penting dan dianggap sebagai pelengkap institusi. Modal sosial adalah juga institusi sosial itu sendiri. Dalam studi tentang sosiologi ekonomi, persoalan modal sosial (social capital) menjadi penting untuk menjelaskan hubungan-hubungan ekonomi yang menghasilkan produk-produk ekonomi dan non-ekonomi (Putnam 2000). Modal sosial ini menjadi syarat untuk diterima menjadi anggota dari sebuah jaringan sosial. Salah satu modal sosial adalah kepercayaan terhadap pihak lain atau trust, kewajiban, norma dan sanksi. Jadi, modal sosial yang dimaksud disini adalah bentuk-bentuk organisasi sosial seperti nilai dan norma, kepercayaan serta jaringan sosial yang mendukung kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Kepercayaan (trust) diajarkan dalam pengertiannya yang berbeda, yaitu bahwa trust sebagai modal spiritual (spiritual capital). Barro (2004) memberikan analogi modal spiritual ini seperti modal manusia (human capital) dalam sistem konvensional. Bourdieu (2002) membedakan antara modal spiritual (spiritualcapital) dengan modal agama (religious capital). Yang pertama mencakup aspek yang lebih luas pada masyarakat yang lebih beragam, dijalankan oleh pola produksi, konsumsi, pertukaran dan konsumsi yang lebih kompleks (extrainstitutional).Sedangkan yang kedua dihasilkan dalam sebuah lembaga yang hirarkis (institutional) (Verter, 2003: 150-174). Victor Nee melalui New Institutionalism sebenarnya hanya melanjutkan konsep modal sosial (social capital) yang sudah diperkenalkan sebelumnya oleh beberapa sarjana seperti Putnam (1993 dan 2000). Modal sosial ini tercipta dari ratusan sampai ribuan interaksi antar orang setiap hari, tidak berlokasi pada diri pribadi atau dalam struktursosial, tapi pada hubungan antar individu. Konsep ini sama dengan institusi-institusi informal dalam kerangka berfikir Nee (2005). Putnam (1993) membagi modal sosial menjadi dua; antara bondingsocial capital dan bridging social capital. Yang pertama mengacu pada modal sosial yang berasal dari identitasidentitas yang bersifat eksklusif seperti kelompok yang berbasis keluarga, suku atau agama. Dan yang kedua bersifat inklusif karena mengacu pada jaringan kelompok yang lebih luas melewati basis keluarga, suku atau agama yang cenderung homogen. Konsep Putnam ini memang yang paling sempit dibanding teoritis yang lain seperti oleh Coleman (1988) yang mendefinisikan modal sosial sebagai “a variety ofdifferent entities, with two elements in common: they all consist of some aspect ofsocial structure, and they facilitate certain actions of actors — whether personal orcorporate actors — within the structure”. Dengan kata lain modal sosial merupakan berbagai entitas yang berbeda, dengan dua elemen yang sama: mereka semua terdiri dari beberapa aspek struktur sosial, dan mereka memfasilitasi tindakan tertentu dari aktor-aktor apakah pribadi atau perusahaan dalam struktur tertentu. Konsep ini memasukkan hubungan-hubungan horizontal dan vertikal sekaligus, serta juga perilaku di dalam dan antara seluruh pihak dalam masyarakat. Dari keterangan tersebut modal sosial itu adalah sebuah produk sosial yang bersifat dinamis (dynamic social construction). Namun begitu, satu hal yang dilupakan oleh teoritis modal sosial seperti yang dikembangkan oleh Putnam adalah apa yang disebut oleh Woolcock (2001:13-14) sebagai lingking social capital, yaitu modal sosial yang melingkupi sekelompok orang-orang yang berbeda-beda dalam kondisi yang berbeda pula sepertimereka yang berada di luar kelompok mereka yang membuat mereka mampu memperoleh sumber daya yang lebih banyak dibanding yang tersedia di masyarakat mereka sendiri. Linking social capital ini semacam tahap ketiga setelah dua modalsosial yang diperkenalkan oleh Putnam, yaitu bonding social capital dan bridging social capital. Seperti sebuah hubungan sosial yang dibangun oleh berbagaikelompok luar yang inklusif sehingga memampukan mereka berhubungan dengan pemerintah. Bourdieu (1986) dalam Sobel (2002: 139) menjelaskan bahwa modal sosial adalah “an attribute of an individual in a social context”. Portes (1998) menjelaskan bahwa ada dua perspektif yang berbeda dalam memahami modal sosial. Pandangan pertama melihat dari perspektif individual seperti yang disebutkan di atas. Sedangkan pandangan kedua menekankan pentingnya peleburan individu dalam lingkungan sosialnya. Pandangan kedua ini melihat modal sosial sebagai sifat dari organisasi sosial, seperti jaringan, norma dan kepercayaan (trust). (Portes 1998: 18). Menurut Putnam (2000:19), modal sosial mengacu pada hubungan antar individu, jaringan sosial (social networks) dan normanorma sosial (social norms) seperti saling memberi dan menerima dan kepercayaan (trust) yang muncul di antara individu. Modal sosial merupakan hubungan-hubungan yang tercipta dan norma-norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat dalam spectrum yang luas, yaitu sebagai perekat sosial (social glue) yang menjaga kesatuan anggota masyarakat secara bersama-sama. Modal sosial ditransmisikan melalui mekanisme-mekanisme kultural, seperti agama, tradisi, atau kebiasaan sejarah (Fukuyama, 2000). Coleman (1988) menjelaskan bahwa jaringan social (social network) merupakan struktur yang memfasilitasi modal sosial. Ada dua bentuk jaringan sosial, yakni jaringan sosial tertutup dan terbuka. Dalam jaringan sosial tertutup (closed social networks) setiap pelaku dapat terkoneksi dengan pelaku lainnya berdasarkan norma yang bertujuan menimalkan dampak negatif dan mekmaksimalkan dampak positif (Arregle et al. 2007). Dalam model jaringan sosial tertutup, terdapat kepercayaan yang tinggi yang membuat biaya transaksi antar anggota rendah karena mereka beranggapan bahwa setiap orang memiliki ketaatan pada norma yang ada. Bagaimanapun, jaringan sosial dengan tingkat kedekatan yang tinggi dapat pula bertindak dalam melarang adanya anggota baru dan modal sosial menjadi instrument dari deskriminasi. Dalam model jaringan terbuka, keterkaitan dengan banyak orang tidak begitu erat, hal ini disebabkan tidak semua aktor mengetahui pelaku lainnya dalam sebuah jaringan sosial (Arregle et al. 2007). Dalam sistem jaringan terbuka (open social networks), setiap anggota kelompok lebih mudah untuk mengakses sumber daya dan informasi baru, namun dalam struktur terbuka ini juga memiliki kesulitan dalam memberikan sanksi terhadap pelaku yang gagal dalam memenuhi kewajibannya, dengan demikian berarti mengurangi kepercayaan terhadap jaringan sosial tersebut. Secara teoritis, jaringan sosial penting dalam memahami tindakan kolektif dalam tiga cara: Pertama, jaringan sosial mengintervensi hingga proses tindakan kolektif, pada saat permulaan dengan membangun atau me-nguatkan identitas pribadi yang menciaptakan potensi untuk berpartisipasi dan di bagian akhir ketika individu memiliki pilihan dan persepsi untuk membuat orang lain mengambil tindakan. Kedua, jaringan sosial menyediakan kaitan antara pendekatan stuktural, yang menekankan aturan tentang identitas, nilai dan jaringan sosial sebagai persetujuan atau penekanan partisipasi dan pendekatan fungsional, yang menekankan pada peran organisasi kemanusiaan. Ketiga, dikarenakan jaringan sosial merupakan bentuk dari pilihan dan persepsi (preference and perception) individu yang membentuk dasar keputusan untuk berpartipasi. Kesemuanya itu membentuk hal yang sifatnya stabil seperti nilai dan identitas ataupun hal yang mudah berubah seperti pilihan dan persepsi (Passy, 2003: 2223) Teori Legitimasi Berger dan Luckmann (1990) dalam Manuaba (2011:226) menyatakan bahwa institusionalisasi bukanlah suatu proses yang stabil walaupun dalam kenyataannya lembagalembaga sudah terbentuk dan mempunyai kecenderungan untuk bertahan terus. Akibat berbagai sebab historis, lingkup tindakantindakan yang sudah dilembagakan mungkin saja mengalami pembongkaran lembaga (deinstitusionalization). Proses-proses institusionalisasi ini acapkali diikuti dengan proses selanjutnya yang disebut legitimasi. Fungsi legitimasi adalah untuk membuat pemahaman yang sudah dilembagakan menjadi tersedia secara objektif dan masuk akal secara subjektif. Legitimasi harus melakukan penjelasanpenjelasan dan pembenaran-pembenaran mengenai unsur-unsur penting dari tradisi kelembagaan. Legitimasi menjelaskan tatanan kelembagaan dengan memberikan kesahihan kognitif dan martabat normatif. Oleh karena itu, legitimasi merupakan hal yang penting bagi sebuah institusi, batasanbatasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku institusi dengan memperhatikan lingkungan. Suchman (1995: 574) menjelaskan bahwa “Legitimacy is a generalized perception or assumtion that the action of an entity are desirable, proper or approriate within some socially constructed system of norms, value, beliefed, and defenitions”.Dengan kata lain bahwa legitimasi adalah generalisasi persespsi atau asumsi bahwa tindakan tersebut sungguh diperlukan, tepat atau cocok dengan sistem konstuksi sosial yang meliputi norma, nilai, keyakinan dan defenisi. Dalam konteks pemerintahan, Coicaud (2002) menjelaskan bahwa legitimasi adalah pengakuan atas kebenaran dalam memerintah, sedangkan Johnson et al. (2006: 57) menjelaskan bahwa legitimasi merupakan konstruksi secara kolektif atas realitas sosial. Dowling dan Pfeffer (1975: 122) memberikan alasan yang logis tentang legitimasi organisasi bahwa Organisasi berusaha menciptakan keselarasan antara nilainilai sosial yang melekat pada kegiataannya dengan norma-norma perilaku yang ada dalam sistem sosial masyarakat dimana organisasi adalah bagian dari sistem tersebut. Selama kedua sistem nilai tersebut selaras, kita dapat melihat hal tersebut sebagai legitimasi organisasi. Ketika ketidak selarasan aktual atau potensial terjadi di antara kedua sistem nilai tersebut, maka akan ada ancaman terhadap legitimasi organisasi. Adapun yang melandasi adanya legitimasi adalah “kontrak sosial” yang terjadi antara organisasi dengan masyarakat dimana organisasi beraktivitas dan menggunakan sumber ekonomi. Shocker dan Sethi (1974: 67) memberikan penjelasan bahwa semua institusi sosial tidak terkecuali organisasi beroperasi di masyarakat melalui kontrak sosial, baik eksplisit maupun implisit, dimana kelangsungan hidup dan pertumbuhannya didasarkan pada: pertama, hasil akhir yang secara sosial dapat diberikan kepada masyarakat luas; kedua, distribusi manfaat ekonomi, sosial atau politik kepada kelompok sesuai dengan kekuasaan yang dimiliki. Di dalam masyarakat yang dinamis, tidak ada sumber kekuasaan (power) institusional dan kebutuhan terhadap pelayanan yang bersifat permanen. Oleh karena itu suatu institusi harus lolos uji legitimasi dan relevansi dengan cara menunjukkan bahwa masyarakat memang memerlukan jasa organisasi dan kelompok tertentu yang memperoleh manfaat dari penghargaan yang diterimanya betul-betul mendapat persetujuan masyarakat. Dowling dan Pfeffer (1975:124) mengatakan bahwa legitimasi tidak dapat didefiniskan hanya dengan mengatakan apa yang legal atai ilegal. Harapan masyarakat terhadap perilaku perusahaan dapat bersifat implisit dan eksplisit (Deegan 2000 : 254). Menurut Deegan (2000) bentuk eksplisit dari kontrak sosial adalah persyaratan legal, sementara bentuk implisitnya adalah harapan masyarakat yang tidak tercantum dalam peraturan legal (uncodified community expectation). Ada tiga alasan yang menyebabkan terjadinya korelasi yang tidak sempurna antara hukum dan norma/nilai sosial (Dowling dan Pfeffer 1975). Pertama, meskipun hukum sering dianggap sebagai refleksi dari norma dan nilai sosial, sistem hukum formal mungkin terlalu lambat dalam mengadaptasi perubahan norma dan nilai sosial di masyarakat. Kedua, sistem legal didasarkan pada konsistensi sedangkan norma mungkin kontradiktif. Ketiga, masyarakat mungkin mentolerir perilaku tertentu tapi tidak menginginkan perilaku tersebut tercantum dalam aturan hukum. Dapat dikatakan bahwa legitimasi merupakan hasil dari proses institusionalisasi, sehingga dampak dari perubahan institusi yang ditandai dengan tingginya ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap legitimasi organisasi. Dalam kondisi ini, legitimasi menjadi penting bagi keberlanjutan organisasi (Suchman, 1995). Legitimasi menjadi sumber, dan organisasi membutuhkannya untuk memperoleh akses ke sumber lingkungan lainnya. Faktor-faktor Institusional dan Modal Sosial yang Membetuk Legitimasi Walaupun institusi dibentuk dari institutionalisasi lingkungan organisasi yang dinyatakan pada level keseimbangan dan kesinambungan, institusi juga merupakan objek perubahan (Scott, 2001; Dowling dan Pfeffer, 1975). Proses perubahan tersebut dapat bersifat incremental dan terputus (Scott, 2001:48) yang bersumber dari faktor eksternal organisasi seperti perubahan politik, ekonomi dan proses sosial atau faktor internal organisasi seperti pemunculan dan penurunan aktor yang memiliki kekuatan besar (powerful actors) atau aktivitas-aktivitas organisasi (Galvin, 2002). Perubahan secara institusional ini menciptakan sumber tekanan pada organisasi yang pada akhirnya memotivasi organisasi untuk berubah. Dalam kaitannya dengan perubahan, institusi dapat menjadi bebeda tergantung pada perubahan yang dilakukan, baik berupa aturan formal dan regulasi yang dapat berubah dalam waktu singkat, atau atau secara informal yang secara mendalam menyatu di dalam budaya masyarakat yang terlihat sulit berubah. Institusi yang berubah secara formal tanpa mempertimbangkan model informal memiliki resiko dalam keberhasilan proses perubahan secara instistusional (Ovin, 2001). Legitimasi Organisasi Legitimasi merupakan konsep yang menjelaskan keberadaan garis batas antara organisasi dan lingkungan sosial-budaya dimana organisasi itu ada dan beraktivitas. Organisasi yang terlegitimasi merupakan representasi dari evaluasi organisasi oleh sistem sosial. Legitimasi organisasi merupakan bentuk penghargaan dari stakehoder yang menilai bahwa organisasi selah sesuai dengan standar atau model tertentu. Ada dua pendekatan dalam memahami keberadaan legitimasi yaitu strategis dan institusional (Suchman, 1995). Pendekatan strategis memandang legitimasi sebagai sumber daya operasional diperolah oleh organisasi dari lingkungan sosialnya dan kemudian menggunakannya memperoleh sumber daya lainnya (Suchman, 1995; Dowling and Pfeffer, 1975). Di sisi lain, yakni perspektif institusional mengadopsi pandangan yan lebih pasif pada organisasi, yang menganggap bahwa organisasi ditentukan oleh lingkungan sosial dan keputusan manajerial dibentuk oleh pemerimaan sistem kepercayaan yang luas (Suchman, 1995). Walaupun penulis kurang sependapat dengan pernyataan kepasifan organisasi, namun tidak dipungkiri bahwa perubahan organisasi melalui tekanan lingkungan sosial melalui proses adopsi dan adaptasi oleh organisasi melalui proses pengambilan keputusan yang merupakan tuntutan atas legitimasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Scott (1991) bahwa organisasi tidaklah pasif dan dapat membuat pilihan strategis, terutama dalam menjelaskan legitimasi. Perbedaan stakeholder pada setiap gradasi lingkungan memberikan berbagai jenis legitimasi ketika menilai kepatuhan organisasi untuk memenuhi persyaratan standar regulasi, normatif, budaya-kognitif dan moral. Pada umumnya organisasi fokus menghadapi tantangan bagaimana memprioritaskan lembaga berfungsi pada tingkat lingkungan yang berbeda. Selain itu, gradasi lingkungan berubah sepanjang waktu dan di banyak tempat (Scott, 2001). Adapun yang menjadi tantangan adalah dalam mengidentifikasikan gradasi lingkungan yang relevan yang dapat dipertimbangkan ketika organisasi menjelaskan legitimasi mereka secara strategis. Dalam menjelaskan proses legitimasi,ada tiga proses yang disebutkan dari kajian lieratur yakni memperoleh, memelihara, dan memperbaiki legitimasi (Suchman,1995:586). Pada penelitian ini, penulis lebih melihat pada proses bagaimanaorganisasi yang beroperasi mendapatkan legitimasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Suchman(1995) yang menjelaskan kaitan proses ini dengan buruknya institusionalisasi lingkungan. Oleh karena itu, pendekatan strategis bahwa proses memperoleh legitimasi yang dinamis paling tepat untuk dipertimbangkan. Selain itu akan diteliti pula faktor-faktor apa saja yang dibutuhkan dalam menjamin terciptanya kebijakan publik yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam kajian literatur, ada beragam tipologi legitimasi tergantung pada konteks yang diteliti dan masalah penelitian yang khusus (Suchman 1995; Dacin, Oliver dan Roy 2007). Bahkan, institusi sebagai sumber legitimasi dapat menjelaskan jenis legitimasi yang diberikan. Scott (2001) memperluas pandangan mengenai institusi dan menganggap sumber legitimasi terdiri darielemen regulasi, norma dan budayakognisi, yang memberikan stabilitas dalam interaksi manusia. Regulasi Legitimasi yang bersumber dari peraturan adalah kesesuaian dengan peraturan, aturan standar dan hukum (Scott, 2003; Zimmerman dan Zeitz, 2002),yang menurut definisi memiliki karakter formal. Pada umumnya, organisasi berbadan hukum seperti pemerintah, asosiasi, organisasi profesi dan yang lainnya, telah menetapkan proses regulasi secara eksplisit (explicit regulative processes) (Scott 1995) yang meliputi aturan, pemantauan dan sanksi jika terjadi ketidaksesuaian (Scott, 1995; Zimmerman dan Zeitz,2002). Ketiga dimensi ini merupakan ukuran dalam penerapan elemen regulasi di dalam organisasi. Dengan demikian, aturan hukum dan regulasi adalah institusi formal yang mewakili sumber legitimasi peraturan dan badan pemerintah yang memberikan kewenangan itu adalah lembaga-lembaga negara diberbagai tingkat regional, lokal, nasional dan internasional. Penelitian sebelumnya menunjuk-kan bahwa regulasi adalah sumber pertama organisasi yang mencoba untuk mendapatkan untuk mendapatkan legitimasi. Misalnya, Delmar dan Shane (2004) me-nemukan bahwa organisasi yang badan hukum dan menjalankan kegiatannya memiliki kemungkinan lebih tinggi kelangsungan hidup. Dengan mendapatkan legitimasi dari sisi regulasi berarti organisasi telah mendapatkan legitimasi secara peraturan untuk menjalamkan operasionalnya. Norma Legitimasi yang berdasarkan norma adalah kepatuhan terhadap norma-norma dan nilai-nilai informal secara luas diterima (Scott, 2003). Dalam hal ini, pertimbangan legitimasi secara normatif sebagai sebuah konstruksi sosial informal yang telah dikembangkan dan dilembagakan seiring dengan waktu dan kebutuhan. Scott (2001) mendefinisikan nilai sebagai konsep-konsep dari yang diinginkan yang berhubungan dengan standar untuk setiap struktur yang ada atau perilaku dapat dibandingkan. Norma mengandung pengertian bagaimana sesuatu harus dilakukan (Scott, 2001). Dengan kata lain, nilai adalah prinsip moral secaraumum dan norma adalah petunjuk konkrit untuk berperilaku. Norma terbentuk dari nilai (values) yang dianut yang menjadi aturan tentang boleh dan tidaknya sebuah perbuatan. Komponen dasar dari norma adalah petunjuk (prescription), evaluasi (evaluation) and kewajiban (obligation) Ligero, 2011). Ketiga dimensi ini merupakan ukuran dalam memahami elemen normatif. Organisasi harus menerapkan tidak hanya sosial norma umum tetapi juga berbagai standar yang berasal dari berbagai aspek profesional yang berbeda (Di Maggio dan Powell, 1983). Budaya-Kognisi Legitimasi yang berdasarkan budaya-kognisi adalah kesesuaian dengan kepercayaan budaya secara luas dipegang dan praktek yang takenfor-granted (diambil begitu saja) (Scott 2001). Elemen kognitif dapat digambarkan sebagai aturan yang menentukan jenis aktor yang memungkinkan ada, apakah struktural fitur yang digunakan, prosedur apa mereka dapat mengikuti, dan apa makna yang berhubungan dengan tindakan ini. Sumber-sumber budaya-kognitif dalam legitimasi adalah asumsi yang taken-forgranted pada sistem sosial (Scott 2001), yang memiliki karakter informal. Menurut Suchman (1995), dimensi kultural-kognitif legitimasi yang paling halus dan paling kuat dan juga yang paling sulit untuk mendapatkan dan memanipulasi. Davis dan Greve (1997:6) menjelaskan bahwa pendekatan kognitif berfokus pada berbagi kerangka pemikiran (shared frameworks) atas penafsiran pelaku, yang memungkinkan mereka untuk memperoleh definisi umum dari situasi tertentu. Dengan demikian, legitimasi berasal dari mengadopsi kerangka acuan umum yang konsisten dengan yang berlaku dalam sistem sosial. Namun dalam perspektif kognitif atau budaya-kognisi tidak boleh dipahami secara keliru, karena fokus kajian bukan pada kognisi individual, tetapi pada realitas taken-forgranted konstruksi sosial yang memandu tindakan organisasi (Zucker, 1977). Adapun dimensi yang digunakan ialah aturan (rules) yang pada dasarnya merupakan pengganti dari realitas sosial dan perumusan (formulas) yang berarti cara mendapatkan (Ligero, 2011). Moral Legitimasi yang bersumber dari moral merupakan penyesuaian terhadap standarstandar sosial tentang benar atau salah. Suchman (1995:579) menjelaskan bahwa yang dijadikan sandaran dalam penilaian adalah apakah perbuatan atau kegiatan adalah hal yang benar untuk dilakukan. Disamping itu, penilaian tersebut, pada gilirannya merefleksikan keyakinan mengenai aktivitas yang dilakukan mengarah kepada kesejahteraan sosial, yang merupakan desain dari sistem nilai dari kontrak sosial. Legitimasi berdasarkan moral berbeda dengan yang bersumber dari kognisi. Pada pendekatan moral, focus kajian ada pada kebenaran yang mendukung lingkungan sosial, sedangkan pada pendekatan kognisi perolehan legitimasi bersifat taken-for-granted antara tujuan organisasi dan kegiatan yang mendukung lingkungan sosial tanpa didasari oleh penilaian yang cermat (Droege, lane dan Spiller, 2011:104). Lebih lanjut Droege, lane dan Spiller (2011:104-105) menjelaskan pembagian moral dalam mewujudkan legitimasi yang terdiri atas konsekuensi, prosedur, struktur dan personal. Legitimasi berdasarkan moral berawal dari usaha organisasi untuk mempertahankan prilaku etisnya hingga pemenuhan respon terhadap tekanan sosial-politik dalam bertindak dalam tanggung jawab yang lebih luas (Long dan Driscoll:2008:178). Legitimasi sebaiknya memperhitungkan moral dominan dan tanggung jawab sosial dalam masyarakat di mana organisasi beroperasi meskipun nilai-nilai organisasi ada yang bertentangan dengan harapan masyarakat (Kennedy dan Fiss, 2009). Kesesuaian terhadap tekanan-tekananyang diberikan oleh difusi harapan sosial baru yang tidak kompatibel dengan arahan institusional (Seo dan Creed,2002), pada gilirannya akan mengganggu institusi dan menghasilkan perubahan nilai-nilai sosial tentang legitimasi sebuah organisasi. Aksi moral merupakan proses dari modal sosial, karena kegiatan komunitas aktor bergerak ke arah perbaikan atas masalah yang ada dan menciptakan kehidupan yang lebih baik (Kang dan Glassman, 2010). Simpulan Basis institusi dan modal sosial me-rupakan hal yang paling penting dalam memahami sumber legitimasi pada organisasi pelayanan publik. Pemahaman pemerintah yang terimplementasi pada model pelayanan publik yang responsif akan memberikan penguatan akan legitimasi tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik akan menjadikan pelayanan publik lebih kaya akan kepentingan publik itu sendiri. DAFTAR PUSTAKA Arregle, J. L., M. A. Hitt, D. G. Sirmon, and P. Very. 2007. The Development of Organizational Social Capital: Attributes of family firms. Journal of Management Studies 44 (1):73-95. Barro, Robert J. 2004. “Spirit of Capitalism: Religion and Economic Development.” Harvard International Review, Winter, 2004. Budiardjo, Miriam, 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi), (PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Coicaud, J.M., 2002. Legitimacy and Politics: Acontobution To Study Of Political Right dan Political Respnsibility. New York : Camcridge University Press. Coleman, J. S., 1988. Social Capital In The Creation Of Human Capital. The American Journal of Sociology 94 (Supplement): S95S120. Dacin, T., Oliver, C., and Roy, J.P., 2007. The Legitimacy of Strategic Alliances: An Institutional Perspective, Strategic Management Journal, 28: 2, 169-189. Ovin, Rasto. 2001. The Nature of Institutional Change in Transition. Post-Communist Economies, 13: 2, 133-146. Dakhli, M., de Clercq, D., 2004. Human Capital, Social Capital, And Innovation: a multi-country study. Entrepreneurship & Regional Development, 16, March, pp. 107– 128. Dasgupta, P., 2005. Economics of Social Capital. Economic Record, 81(S1), S2-S21. Daubon, R.E. and Saunders, H.H., 2002. Operationalising Social Capital: A Strategy to Enhance Communities’ ‘Capacity to Concert’. International Studies Perspectives, 2, 176-191. Davis, G. F., and Greve. H.R., 1997. Cooperate Elite Networks And Governance Changes In The 1980s. American Journal of Sociology, 103, 1-37. Deegan C, (2000), Finacial Accounting Theory, Sydney :McGraw-Hill Delmar, F. and Shane, S., 2004. Legitimating First: Organizing Activities And The Survival Of New Ventures. Journal of Business Venturing 19, p. 385‐410. Dowling, J. and Pfeffer, J. 1975, 'Organisational Legitimacy: Social Values And Organisational Behaviour', Pacific Sociological Review, Vol. 18, Iss. 1, pp. 122136. Droege, S. Lane, M. And Spiller, S. 2011, Intersecting Three Muddy Roads: Stability, Legitimacy, and Change, Journal of managerial Isuues, Vol. XXIII (1):96:112 Farjoun, M. 2010. “Beyond Dualism: Stability and Change as Duality.” Academy of Management Review 35(2): 202-225. Fukuyama, F., 2002. Social Capital and Development: The Coming Agenda. SAIS Review, XXII(1), 23-37. -------------------. 2000. “Social Capital”, in Harrison, L., Huntington, S. (ed.) (2000) Culture Matters: How Values Shape Human Progress. New York: Basic Books. Galvin, T.L. 2002. Examining Institutional Change: Evidence from the Founding Dynamics of U.S. Health Care Interest Associations. The Academy of Management Journal, 45: 4, 673-696. Grootaert, C. & van Bastelaer, T., 2002. Introduction and overview. In C. Grootaert, van Bastelaer, T. (Eds.), The role of social capital in development (pp. 118).Cambridge, UK. Cambridge University Press. Harvey, B., & Schaefer, A., (2001. Managing Relationships With Environmental Stakeholders: A study of U.K. water and electricity utilities. Journal of Business Ethics, 30, 243–260. Idemudia, U. 2007. “Community Perceptions and Expectations: Reinventing the Wheels of Corporate Social Responsibility Practices in the Nigerian Oil Industry.” Business and Society Review 11(23): 369-405. Isham, J. Kelly, T. & Ramaswamy, S., 2002. Social Capital and well-being in developing countries: an introduction. In J. Isham, Kelly, T. & Ramaswamy, S. (Eds.), Social capital and economic development: Well-being in developing countries (pp. 3-17). Cheltenham, UK: Edward Elgar. Jeyariaj, A., C. Charles, C. Balser, and G. Griggs. 2004. Institutional Factors Influencing E-Business Adoption. Johnson, C., Dowd, T. J. and Ridgeway, C. L., 2006. "Legitimacy as a Social Process," Annual Review of Sociology (32) 1, pp. 5378. Kennedy, M. T. and P. C. Fiss. 2009. “Institutionalization, Framing, and Diffusion: The Logic of TQM Adoption and Implementation Decisions Among U.S. Hospitals.” The Academy of Management Journal 52(5): 897-918. Landry R., Amara N., Lamari M., 2002. ‘Does Social Capital Determine Innovation? To What Extent?’ Technological Forecasting and Social Change, Vol. 69, pp. 681–701. Long, B. S, and C, Driscoll, 2008. Codes of ethics and the pursuit of organization legitimacy: Theorical, and empirical constributions, Journal of Bussiness ethics, 77:173-189 Ligero, F. Rigquel, 2011. Social legitimacy of Golf tourism: An Aplication to th e Golf Courses of Andalusia, Enlghtening Turism. A Pathmaking Journal, Vol 1 (1) : 152-173 Manuaba, I. B. Putera, 2011. Memahami Teori Konstruksi Sosial, Jurnal Masyarakat Kebudayaan Dan Politik, Volume 21, Nomor 3:221-230 Narayan, D. 2002. Bonds and bridges: Social capital and poverty. In J. Isham, Kelly, T. & Ramaswamy, S. (Eds.), Social capital and economic development: Well-being in developing countries (pp. 58-79). Cheltenham, UK: Edward Elgar. Navarro, J., Ruiz, M. (1997). Teoría Institucional y Teoría de la Organización. Anales de Economía y Administración de Empresas, 5, 135-152. Nee, Victor, 2005. “The New Institutionalisms in Economics and Sociology,” in Neil J. Smelser and Richard Swedberg (eds), (2005). Handbook of Economic Sociology. Russel Sage Foundation: Princeton University Press. North, Douglas C. 1991. “Institutions.” Jorunal of Economic Perspectives 5:97-112. ---------------------.1993. “Institutions and Credible Commitment.” Journal of Institutional and Theoretical Economics 145: 11-23. Ovin, Rasto. 2001. The Nature of Institutional Change in Transition. Post-Communist Economies, 13: 2, 133-146. Passy, F. 2003. Social networks matter. But how? In M. Diani & D. McAdam (Eds.), Comparative Politics. New York; NY: Oxford University Press. Pfeffer, J. 2005. Great Minds in Management, edited by K. G. Smith and M. A. Hitt, New York, NY: Oxford University Press. Portes, Alejandro, 2006. “Institutions and Development: A Coceptual Reanalysis.” Population and Development Review 32 (2): 233-262 (June). -----------------------. 1998. ‘Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology’, Annual Review of Sociology, vol. 24, pp.1-24. Putnam, Robert D. 1993. “The Prosperous Community: Social Capital and Public Life”. The American Prospect, 4: 13. ------------------------. 2000. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon and Schuster. Sánchez, A. Vargas, Ligero¸ F. Riquel, 2010. An institutional approach to the environmental management systems of golf courses in Andalusia, European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation Vol. I, Issue 1, pp. 24-38, Scott, W.R. 1995, Institutions and Organizations, Thousand Oaks, CA: Sage, 1st edition. Scott, W.R. 2001, Institutions and Organizations, Thousand Oaks, CA: Sage, 2nd edition. ------------------. 2003, Organizations: Rational, Natural and Open Systems. New Jersey: Prentice Hall, 5th edition. Scott, W.R. and Meyer, J.W. 1991. The Organization of Societal Sectors: Propositions and Early Evidence. In W. W. Powell and P. J. DiMaggio (Eds.), in The New Institutionalism in Organizational Analysis, 108-140. Chicago: The University of Chicago Press. Schein, E.H. 2004, Organizational Culture And Leadership, third edition, San Fransisco: Jossey-Bass. Selznick, Philip 1949. TVA and the Gross Roots. Bekeley and Los Angeles: University of California Press. Seo, M. and D. Creed. 2002. “Institutional Contradictions, Praxis, and Institutional Change: A Dialectical Perspective.” Academy of Management Review 27(2): 222247. Shocker, A. D. & Sethi, S.P. 1974, An approach to incorporating social preferences in developingcorporate action strategies in The Unstable Ground: Corporate Social Policy in a Dynamic Society, ed. S.P. Sethi, (pp. 6780), Melville, California. Sobel, J. 2002, ‘Can we trust social capital?’, Journal of Economic Literature, vol. XL, pp. 139-154. Suchman, Mark, C., 1995. Managing Legitimacy: Strategies and Institutional Approach, Academy of Management Review, 20 (3). 571-610 Swanson, E.B., and Ramiller, N.C. 1997.The organizing vision in information systems innovation.Organization Science, 8 (5). 458– 474. Teo, H., K. Wei, and I. Benbasat. (2003). Predicting intention to adopt interorganizational linkages: An institutional perspective. MIS Quarterly 27 (1) : 19–49. Toboso, F. (2001). "Institutional Individualism and Institutional Change: the Search For a Middle Way Mode of Explanation", in Cambridge Journal of Economics, vol. 25, no.6, November, p. 765-784. Uphoff, Norman. 1986. Local Instutional Development; An Analitical Sourcebook. West Hartford. Kumarian Press. Verter, Bradford. Spiritual capital: Theorizing Religion with Bourdieu against Bourdieu Sociological Theory, 21(2), 50-174. (2003). Wallner, Jennifer Policy Studies Journal; Aug 2008; 36, 3; ProQuest Research Library pg. 421 Whitley, Richard 1996. “Business Systems and Global Commodity Chains: Competing or Complementary Forms of Economic Organisation?” Competition and Change 1 (4): 411-25. Woolcock, M. (2002). Social capital in theory and practice: Where do we stand? In J. Isham, Kelly, T. & Ramaswamy, S. (Eds.), Social capital and economic development: Well-being in developing countries (pp. 1839). Cheltenham, UK: Edward Elgar. Zimmerman, M.A. and G.J. Zeitz (2002), Beyond Survival: Achieving New Venture Growth by Building Legitimacy, Academy of Management Review, 27: 3, 414-443.