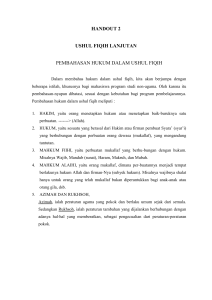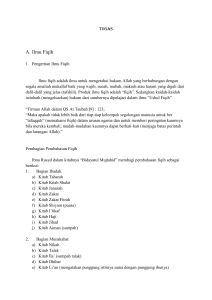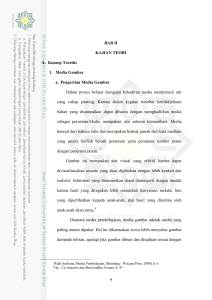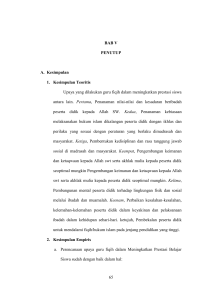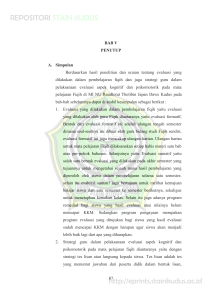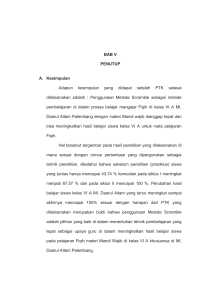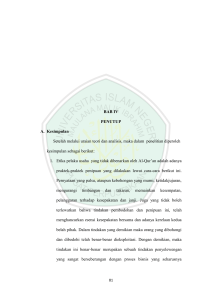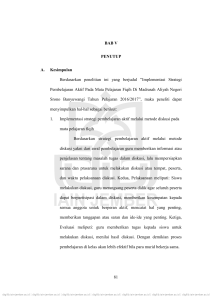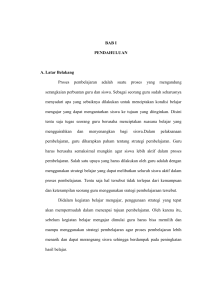Uploaded by
rozaqfebrian04
Hukum-Hukum Syar'iyyah II: Hukum Wadh'i, Mahkum Fih, Mahkum 'Alaih
advertisement

MAKALAH HUKUM-HUKUM SYAR’IYYAH II Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Metodologi Studi Fiqih Dosen Pengampu : Muhammad Bahauddin, S.Hum, M.Pd Disusun Oleh Kelompok 7 : 1. Muhammad Riza Afthoni (2011010044) 2. Ika Ariyani Mualifah (2011010045) 3. Ab Rozak Febriansyah (2011010046) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS FAKULTAS TARBIYAH PROGRAM STUDI BIMBINGAN & KONSELING PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2020 1 KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul Hukum-Hukum Syar’iyah II ini tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan dari makalah ini adalah untuk memenuhi tugas Muhammad Bahauddin, S.Hum, M.Pd. Pada Mata Kuliah Metodologi Studi Fiqih. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang Hukum-Hukum Syar’iyah II bagi para pembaca dan juga bagi penulis. Saya mengucapkan terima kasih kepada Muhammad Bahauddin, S.Hum, M.Pd. Selaku Dosen Mata Kuliah Metodologi Studi Fiqih. Yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang saya tekuni. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini. Saya menyadari, makalah yang saya tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan saya nantikan demi kesempurnaan makalah ini. Kudus, 27 September 2020 2 DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ................................................................................... 1 KATA PENGANTAR ................................................................................. 2 DAFTAR ISI ................................................................................................ 3 BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ 4 A. Latar Belakang ................................................................................ 4 B. Rumusan Masalah ........................................................................... 4 C. Tujuan Penulisan ............................................................................. 4 BAB II PEMBAHASAN ............................................................................. 5 A. Pengertian Hukum Wadh’i ............................................................. 5 B. Macam-Macam Hukum Wadh’i ..................................................... 6 C. Pengertian Mahkum Fih ................................................................ 12 D. Pengertian Mahkum Alaih ............................................................ 15 BAB III PENUTUP ................................................................................... 19 A. Kesimpulan ................................................................................... 19 B. Saran ............................................................................................. 19 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................ 21 3 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat terlepas dari aturan dan norma-norma yang berlaku menurut hukum syara’. Hukum syara’ itu ada dua macam yaitu hukum syara’ yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang mengandung tuntutan dan kebolehan yang dinamakan “hukum taklifi” dan yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang mengandung persyaratan, sebab atau mani’ dinamakan ‘hukum wadh’i”. B. Rumusan Masalah 1. Apa pengertian Hukum wadh’i? 2. Apa macam-macam hukum wadh’i ? 3. Apa pengertian Mahkum Fih ? 4. Apa pengertian Mahkum Alaih ? C. Tujuan Penulisan 1. Untuk mengetahui pengertian Hukum wadh’i 2. Untuk mengetahui macam-macam hukum wadh’i 3. Untuk mengetahui pengertian Mahkum Fih 4. Untuk mengetahui pengertian Mahkum Alaih 4 BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Hukum Wadh’i Hukum wadh’i adalah hukum yang bertujuan menjadikan sesuatu adalah sebab untuk sesuatu atau syarat baginya atau penghalang terhadap sesuatu. 1 Bila firman Allah menunjukkan atas kaitan sesuatu dengan hukum taklifi, baik bersifat sebagai sebab, atau syarat, atau penghalang maka ia disebut hukum wadh’i. Di dalam ilmu hukum Ia disebut pertimbangan hukum. 2 Adapun contohnya yaitu : 1. Firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab: )6:(المائدة....ق َّ َيآاَيُّ َهاالَّ ِذيْنَ ا َمنُ ْوآاِذَا قُ ْمت ُ ْم اِلَى ال. ِ ِصلو ِة فَا ْغ ِسلُ ْوا ُو ُج ْو َه ُك ْم َوا َ ْي ِد َي ُك ْم اِلَى ْال َم َراف Artinya :”Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri untuk mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai kepada suku.”(QS. Al-Ma’idah:6). Ayat di atas dapat dipahami bahwa mendirikan shalat menjadi sebab untuk mewajibkan wudhu atau menjadikan sesuatu adalah sebab terhadap sesuatu. 3 2. Firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai syarat: )ى َعدْ ٍل(روه احمد ْ َََل نِكَا َح ا ََِّل بِ َو ِلي ٍ َوشَا ِهد Artinya :”Tidak syah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.” (HR. Ahmad) Dua orang saksi menjadi syarat untuk sahnya pernikahan itulah yang dimaksud dengan menentukan sesuatu menjadi sahnya sesuatu. 4 A. Syafi’i Karim, FIQIH USHUL FIQIH, Cet.I, (Bandung:Pustaka Setia, 1997) hlm. 107 2 Rachmat Syafe’i, Ilmu USHUL FIQIH, Cet.IV, (Bandung: Pustaka Setia, 2010) 1 hlm. 312 A. Syafi’i Karim, FIQIH USHUL FIQIH, Cet.I, (Bandung:Pustaka Setia, 1997) hlm. 107 4 Ibid, hlm.108 3 5 3. Contoh mani’ atau penghalang seperti tercantum dalam hadist yang berbunyi : )ش ْيء (رواه النسائ والدا رقطنى َ ث ِ المي َْرا ِ َْس ِل ْلقَاتِ ِل ِمن َ لَي Artinya:”Tidak sedikitpun bagian orang yang membunuh dari harta warisan (yang terbunuh)”. (HR. Nasa’i dan Daraquthi dari Amrin bin Suaib dari ayahnya dan dari anaknya). Hadist tersebut menunjukkan bahwa membunuh sebagai penghalang untuk mendapatkan warisan. 5 B. Macam-Macam Hukum Wadh’i Para ulama fiqih menyatakan bahwa hukum wadh’i itu ada lima macam, yaitu : 1. Sebab a. Pengertian Sebab Sebab menurut bahasa adalah sesuatu yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang lain. 6 Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang dijadikan oleh syar’i sebagai tanda atas musababnya dan mengkaitkan keberadaan musabab, dengan ketiadaannya. 7 Hukum syara’ kadang-kadang diketahui melalui tanda yang menunjukkan bahwa perbuatan mukallaf. Misalnya: Perbuatan zina itu menjadi menyebabkan kewajiban seseorang dikenai hukuman dera 100 kali, tergelincirnya matahari menjadi sebab wajibnya sholat dhuhur, dan terbenamnya matahari menjadi sebab wajibnya shalat magrib. Apabila perzinaan tidak dilakukan, maka hukuman dera tidak dikenakan. Apabila matahari belum tergelincir, maka shalat dhuhur belum wajib. Dan apabila matahari belum terbenam, maka shalat mahgrib belum wajib. 8 Rachmat Syafe’i, Ilmu USHUL FIQIH, Cet.IV, (Bandung: Pustaka Setia, 2010) hlm. 313 6 Dikutip oleh Abd. Rahman Dahlan dari kitab al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam juz III, Al-Amidi, hlm.89 7 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu USHUL FIQIH, Terj. Moh. Zuhri, cet. I, (Semarang: Dina Utama, 1994) hlm. 171 8 Nasrun Haroen, USHUL FIQH 1, Cet.I, (Jakarta: Logos,1996), hlm.260 5 6 Dengan demikian terlihat hukum wadh’i dalam hal ini adalah sebab, dengan hukum taklifi, keberadaan hukum wadh’i itu tidak menyentuh esensi hukum taklifi. Hukum wadh’I hanya sebagai petunjuk atau indikator untuk pelaksanaan hukum taklifi. Akan tetapi, para ulama’ ushul fiqih menetapkan bahwa sebab itu harus muncul dari nash, bukan buatan manusia. b. Pembagian sebab Secara garis besar sebab ada dua macam, yaitu: 1) Sebab yang tidak termasuk perbuatan mukallaf. Seperti dalam contoh tibanya waktu shalat dan menimbulkan wajibnya shalat. 9 Dalam firman Allah SWT.: َّ ص َل ة َ ِلدُلُ ْو ِك ال ...ش ْم ِس َّ ا َ ِق ِم ال Artinya:” dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir….( Q.S. Al-isra’ : 78 ) 2) Sebab yang berasal dari perbuatan mukallaf. Seperti pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan adanya qishas. Dalam firman Allah SWT. : .....اص ِفى القَتْلَى ُ ص َ َيآ أ َ ُّي َهاالَّ ِذيْنَ َءا َمنُ ْوا ُك ِت َ ب َعلَ ْي ُك ْم ْال ِث “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuhHai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh….”( al-Baqarah:178) 2. Syarat a. Pengertian syarat Syarat ialah sesuatu yang berada di luar hukum syara’, tetapi keberadaannya hukum syara’ bergantung kepadanya. Apabila syarat tidak ada, hukum pun tidak ada, tetapi, adanya syarat tidak mengharuskan adanya hukum syara’. 10 9 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu USHUL FIQIH, Terj. Moh. Zuhri, cet. I, (Semarang: Dina Utama, 1994) hlm. 171 Rachmat Syafe’i, Ilmu USHUL FIQIH, Cet.IV, (Bandung: Pustaka Setia, 2010) hlm. 313 10 7 Misalnya: Wudlu adalah salah satu syarat sahnya shalat. Sholat tidak dapat dilaksanakan, tanpa berwudlu terlebuh dahulu. Akan tetapi apabila seseorang berwudlu, ia tidak harus melaksanakan shalat. b. Pembagian syarat Para ulama’ memberi uraian tentang pembagian syarat dengan berbagai tinjauan, akan tetapi yang terpenting ialah bahwa ditunjau dari segi penetapannya sebagai hukum syara’, syarat dibagi menjadi dua bagian yaitu : 1) Syarat Asy-syar’iyyah Ialah syarat yang menyempurnakan sebab dan menjadikan efeknya yang timbul padanya yang ditentukan oleh syara’. 11 Misalnya: akad nikah dijadikan syarat halalnya pergaulan suami istri namun agar akad nikah itu sah disyaratkan dihadiri oleh dua orang saksi. Dengan demikian apabila akad atau tindakan hukum tidak akan menimbulkan efekya kecuali apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi. 12 2) Syarat Al-Ja’liyyah Ialah syarat yang menyempurnakan sebab dan menjadikan efeknya yang timbul padanya yang ditentukan oleh mukallaf. Contohnya , seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya dengan mengatakan: “ jika engkau mengulangi perkataan dusta itu, maka talakmu jatuh satu”. Dengan demikian talak tidak akan menimbulkan efeknya kecuali tidak terpenuhi syarat talak. 3. Ash-Shihah, Al-Buthlan dan Al-Fasad a. Pengertian Ash-Shihah, Al-Buthlan dan Al-Fasad 11 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu USHUL FIQIH, Terj. Moh. Zuhri, cet. I, (Semarang: Dina Utama, 1994) hlm. 173 12 Ibid, hlm. 173 8 1) Ash-Shihah secara bahasa Sah atau Shihah ( ) الصححةatau shahih ( ) الصحيحlawan dari ( ) المريضةyang artinya sakit. Secara istilah, para ahli ushul fiqih merumuskan definisi sah dengan : 13 ْ ت ََرتُّبُ ثَ ْم َرتِ ِه ْال َم ُ ش ْر َّ ار ال َّ سبَبُ َوت ََوفَّ َر ال ش ْر ِ ط َوا ْنتَفَى ال َمانِ ُع ت ََرت َّ َب َّ ص َل ال ُ َت اْآلث َ فَإِذَا َح.طلُ ْوبَ ِة ِم ْنهُ ش َْرعًا َعلَ ْي ِه ِعيْةة ُ َعلَى ال ِف ْع ِل “ Tercapainya sesuatu yang diharapkan secara syara’, apabila sebabnya ada, syarat terpenuhi, halangan tidak ada, dan berhasil memenuhi kehendak syara’ pada perbuatan itu. Maksudnya, sesuatu perbuatan dikatakan sah apabila terpenuhi sebab dan syaratnya, tidak ada halangan dalam melaksanakannya, serta apa yang diinginkan syara’ dari perbuatan itu berhasil dicapai. Misalnya: seseorang melaksanakan shalat dengan memenuhi rukun, syarat, dan sebab, serta orang yang shalat itu terhindar dari mani’ atau terhalang. Apabila shalat dhuhur akan dilakdanakan, sebab wajibnya shalat itu telah ada yaitu matahari telah tergelincir, orang yang akan shalat itu telah berwudlu, dan tidak ada mani’ dalam mengerjakan shalat tersebut maka shalat yang dikerjakan tersebut sah. 14 2) Al-Bathl secara etimologi batal yang dalam bahasa arabnya albuthlan ( ) البطلنyang berarti rusak dan gugur hukumnya. Secara terminologi menurut Mushthafa Ahmad al-Zarqa’, yang mengatakan batal adalah : 15 َ َار ِه فِى ن َّ ف ال ع ِ تر ُّ ص َ ش ْر ِعي ِ َع ْن اِ ْعت َ َب َ َّ ت َ َج ُّزد ُ الت ِ َ ار ِه َوآث ِ ظ ِر ال ٍش ْر “ Tindakan hukum yang bersifat syar’i terlepas dari sasarannya, menurut pandangan syara’.” Maksudnya, tindakan hukum yang bersifat syar’i tidak memenuhui ketentuan yang ditetapkan oleh syara’, sehingga apa yang dikehendaki syara’ dari perbuatan tersebut lepas sama sekali (tidak tercapai). Misalnya suatu perbuatan tidak memenuhi rukun 13 14 Ibid, hlm.270 Ibid, hlm.27 15 Dikutip oleh Nasrun Haroen dari kitab al Makhal al-Fiqhi al-‘Am jilid I, Mushthafa Ahmad al-Zarqa, hlm.687 9 atau tidak memenuhi syarat, atau suatu perbuatan dilaksanakan ketika ada mani’ (penghalang). Perbuatan seperti itu dalam pandangan syara’ tidak sah (bathl). Misalnya, dalam persoalan ibadah yaitu orang yang melaksanakan ibadah sholat harus memenuhi rukun dan syaratnya, apabila ada penghalang seperti haid atau nifas maka sholatnya tidak sah atau batal. Sedangkan dalam bidang muamalah, misalnya dalam transaksi jual beli apabila yang melakukannya adalah orang yang belum atau tidak cakap bertindak hukum (seperti anak kecil atau orang gila) maka hukum jual beli tersebut tidak sah. Dengan demikian baik dalam bidang ibadah maupun dalam bidang muamalah, keabsahan suatu perbuatan ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya rukun, syarat, dan penyebab perbuatan itu, dan tidak mani’ untuk melaksanakan perbuatan itu. Tetapi apabila perbuatan itu tidak memenuhi syarat, rukun, dan sebabnya belum ada, atau ada mani’, maka perbuatan itu menjadi batal. 16 Disamping istilah sah dan batal, dalam fiqih islam juga dikenal dengan istilah fasad, yang posisinya diantara sah dan batal. 3) Al-Fasad Secara etimologi, fasad ( ) الفسادberarti ”perubahan sesuatu dari keadaan yang semestinya (sehat).” Dalam bahasa indonesia berarti “rusak”. Dalam pengertian terminologi menurut jumhur ulama bahwa antara batal dan fasad mengandung esensi yang sama, yang berakibat kepada tidak sahnya perbuatan itu. Apabila sesuatu perbuatan tidak memenuhi syarat, rukun, dan tidak ada sebabnya, atau ada mani’ terhadap perbuatan tersebut, maka perbuatan itu disebut fasad atau batal. 17 Menurut ulama Hanafiyyah juga mengemukakan hukum lain yang berdekatan dengan batal, yaitu fasad. Menurut mereka fasad adalah “terjadinya suatu kerusakan dalam unsur-unsur akad.” Artinya, akad itu pada dasarnya adalah sah, tetapi sifat akad itu tidak sah. Misalnya, melakukan jual beli ketika panggilan shalat 16 17 Nasrun Haroen, USHUL FIQH 1, Cet.I, (Jakarta:Logos, 1996), hlm.273 Ibid, hlm.273 10 jum’at berkumandang. Jual beli dan shalat jum’at sama-sama memiliki dasar hukum. Akan tetapi jual beli itu dilaksanakan pada waktu yang sifatnya terlarang untuk melakukan jual beli, maka hukumnya menjadi fasad atau rusak. 18 4) ‘Azimah dan Rukhshah ‘Azimah adalah hukum-hukum yang disyari’atkan oleh Allah kepada seluruh hambanya sejak semula. Maksudnya belum ada hukum sebelum hukum itu disyari’atkan oleh Allah. Misalnya, jumlah shalat dhuhur adalah empat reka’at. Jumlah reka’at ini ditetapkan Allah sejak semula, dimana tidak ada hukum lain yang menetapkan jumlah reka’at shalat dhuhur. Hukum tentang shalat dhuhur tersebut adalah empat reka’at, disebut dengan ‘Azimah. 19 Adapun yang dimaksud al-Rukhshah sebagian ulama’ ushul fiqih ialah : 20 ُ َما صة ِ ع ِمنَ األَحْ ك َِام ِل ْلت َْخ ِفي َ ش ِر َ ْف َع ِن ال ِعبَا ِد فِي أَحْ َوا ِل خَا “Hukum-hukum yang disyari’atkan untuk keringanan bagi mukallaf dalam keadaan tertentu.” Adapun contonya yaitu : a. Rukhshah untuk melakukan perbuatan yang menurut ketentuan syari’at yang umum diharamkan, karena darurat atau kebutuhan. Contohnya, boleh memakan daging babi jika keadaan darurat, diman tidak terdapat makanan selain itu yang jika tidak dimakan maka jiwa seseorang akan terancam. Berdasarkan firman Allah : 21 ....وقد فصا ل لكم ما حرمعليكماَل مااضطر رتماليه 18 Ibid, hlm.273 Rachmat Syafe’i, Ilmu USHUL FIQIH, Cet.IV, (Bandung: Pustaka Setia, 2010) hlm. 315 20 Nasrun Haroen, USHUL FIQH, Cet.I, (Jakarta: Logos, 1996) hlm.276 19 21 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu USHUL FIQIH, Terj. Moh. Zuhri, cet. I, (Semarang: Dina Utama, 1994) hlm. 176 11 Artinya:…”padahal sesungguhnya Allah yelah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya…” (QS. Al-An’am:119) b. Rukhshah untuk meninggalkan yang menurut aturan syri’at yang umum diwajibkan, karena kesulitan melaksanakannya. Contohnya, barang siapa dalam keadaan sakit atau berpergian pada bulan ramadhan, maka ia diperbolehkan untuk buka puasa. Sebagaimana firman Allah : 22 شفَ ٍر فَ ِعدَّة ِم ْن اَي ٍَّام اُخ ََر َ فَ َم ْن َكانَ ِم ْن ُك ْم َم ِر ْيضًا ا َ ْو َعلى Artinya: “…Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka puasa), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain…” (QS. Al- Baqarah: 184). C. Mahkum Fiih Mahkum Fiih adalah perbuatan-perbuatan orang mukallaf yang dibebani suatu hukum (perbuatan hukum). 23 Para ulama ushul fiqih menyatakan bahwa yang dimaksud dengan mahkum fih ) ) فِ ْي ِها َ ْل َمحْ ُك ْو ُمadalah objek hukum, yaitu perbuatan orang mukallaf yang terkait dengan titah syari’ (Allah dan Rasul-Nya), yang bersifat tuntutan mengerjakan, tuntunan meninggalkan suatu pekerjaan, memilih suatu pekerjaan, dan bersifat syarat, sebab, halangan, azimah, rukhshah, sah, serta batal. Jadi, mahkum fih itu merupakan hasil perbuatan manusia yang mukallaf erat hubungannya atau bersangkutan dengan hukum syara’ agama Islam. Misalnya perbuatan manusia yang mukallaf berhubungan dan berkaitan dengan aturan agama Islam, antara lain: 1. Masalah menyempurnakan janji bagi mukallaf, adalah mahkum fih, sebab bertalian dengan ijab, maka hukumnya adalah wajib. 22 23 Ibid, hlm.177 Op.cit., Hasbiyallah, hal. 41. 12 2. Menyangkut masalah tidak dilaksanakan terhadap manusia, adalah mahkum fih, dan bertalian dengan ketentuan Allah dalam firman-Nya: س َ َوَلَ ت َ ْقتُلُو النَّ ْف Artinya: “Janganlah kamu membunuh manusia.” 3. Menyangkut perbuatan manusia, mengenai mengerjakan puasa atau tidak melaksanakan puasa pada bulan Ramadhan bagi orang yang sakit atau orang musafir/dalam prerjalanan jauh, maka masalah itu adalah mahkum fih, bertalian dengan masalah ibadah. Dengan uraian-uraian di atas, jelaslah bahwa apabila diperhatikan semua perbuatan manusia itu ada hubungannya dengan hukum syara’. Berarti semua perbuatan manusia yang mukallaf erat kaitannya dengan hukum syara’, dan semua itu disebut Mahkum Fih dalam hukum Islam. Para kalangan madzab Hanafi yang berpendapat tidak akan terjadi takhlif sebelum tercapai syarat sahnya takhlif mengemukakan alasan : a. Kalau terjadi takhlif sebelum tercapai syarat sah takhlif berarti takhlif tidak dapat dilaksanakan, sedangkan takhlif yang tidak dilaksanakan adalah batal. b. Dalam ucapan Rasulullah ketika mengangkat Muadz bin Jabal menjadi Gubernur Yaman beliau berkata: “Ajaklah mereka (menuturkan) syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah rasul Allah. Jika mereka telah menerimanya beri tahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Kalau mereka telah mnerimanya beri tahukan Allah mewajibkan zakat atas harta kekayaan dari orang yang kaya untuk diserahkan kepada yang miskin dari mereka.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas) Hadits ini menunjukkan bahwa kewajiban shalat dan zakat bergantung kepada penerimaan terhadap ajakan dan kalau mereka tidak menerima berarti tidak wajib bagi mereka. Alasan ini dijawab bahwa yang dimaksud menerima kewajiban shalat dan 13 zakat, tetapi kewajiban menerima iman karena tidak mungkin menerima kewajiban tanpa menerima iman. c. Semua ibadah orang yang kafir tidk diterima karena ibadah memerlukan niat, sedangkan niat dari orang yang kafir tidak sah kecuali terlebih dahulu beriman. d. Perintah melaksanakan ibadah untuk memperoleh pahala, sedangkan orang kafir tidak berhak menerima pahala. e. Kalau orang yang kafir dibebankan melaksanakan shalat tentunya mereka dikenakan hukuman di dunia sebagaimana seorang muslim yang meninggalkan sholat. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pendapat pertama adalah yang terkuat dalilnya karena didukung oleh dalil Al-Quran yang menunjukkan bahwa orang yang kafir masih dibebani ibadah. Karena itu, mereka mendapat hukuman tambahan di akhirat yang berati kebolehan takhlif sekalipun syarat belum tercapai seperti yang dikemukakan oleh madzab Syafi’i. Kalau dilihat dari segi pelaksanaan hukuman di dunia, orang yang kafir itu tidak dituntut hukuman, tetapi hukumannya hanya di akhirat. Keduanya dilihat dari segi pelaksanaan hukuman dunia dan akhirat hanya berbeda tenntang hukuman akhirat.24 Telah menjadi ijma’ seluruh ulama bahwa tidak ada pembebanan selain pada pembuatan orang mukallaf. Oleh karena itu, apabila syar’i mewajibkan atau mensunnahkan suata perbuatan kepada seorang mukallaf, maka beban itu merupakan perbuatan yang harus dikerjakan. Demikian juga apabila syar,i mengharamkan atau memakruhkan sesuatu, maka beban tersebut juga merupakan perbutan yang harus ditinggalkan. Perbuatan yang dibebankan (mahkum bih) kepada orang mukallaf itu mempunyai tiga syarat sebagai berikut: a. Perbutan itu diketahui oleh orang mukallaf secara sempurna, sehingga ia dapat mengerjakannya sesuai dengan tuntutan, 24 Khairul Umam, dkk, Ushul Fiqih 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), cet. 2, hal. 327-333. 14 b. Hendaklah diketahui bahwa pembebanan itu berasal dari yang mempunyai kekuasaan memberi beban dan dari pihak yang wajib diikuti segala hukum-hukum yang dibuatnya, c. Perbuatan itu adalah perbuatan yang mampu dikerjakan atau ditinggalkan, sehingga tidak dibenarkan memberi beban yang mustahil untuk dilaksanakan. Manusia tidak diperintahkan mengerjakan perbuatan yang tidak mungkin (mustahil) dapat dilakukan, sebagaimana firman Allah SWT: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupanya”. (QS.Al-Baqarah: 286). Namun demikian, didalam al-Qur’an dan al-Hadits terdapat keterangan yang menuntut suatu perbuatan diluar kemampuan manusia, seperti berjihat dengan jiwa dan harta, atau bersabar dan tidak suka marah. Bahkan seluruh ibadah yang diperintahkan oleh Allah akan teras berat dan beban bagi manusia yang tidak mengenal hakikat hidup ini. Sebagaimana Rasullullah bersabda: Artinya: “surga diliputi oleh hal-hal yang dibenci, sedang neraka diliputi oleh hal-hal yang menyenangkan.” 25 D. Mahkum ‘Alaih Mahkum ‘alaih ialah orang-orang mukallaf yang dibebani hukum. Adapun syarat-syarat sahnya seorang mukallaf menerima beban hukum itu ada dua macam, yakni: 1. Sanggup memahami khitab-khitab pembebanan atau tuntutan syara’ yang terkandung dalam al-Qur’an dan as-Sunnah, baik secara langsung maupun melalui orang lain. Oleh karena itu, orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memahami khitab syar’i tidak mungkin untuk melaksanakan suatu taklif (pembebanan), 2. Mempunyai kemampuan menerima beban. Dasar pembebanan hukum bagi seorang mukallaf adalah akal dan pemahaman. Kemampuan seseorang untuk menerima kwajiban dan mnerima hak oleh para ulama ushuliyyun dibagi kepada dua macam, yaitu: 25 Op.Cit., Hasbiyallah, Hal. 41-42. 15 a. Ahliyatul wujub, yaitu kepantasan seseorang untuk memberi hak dan kewajiban. Kepantasan ini ada pada setiap manusia, baik lakilaki maupun perempuan, kanak-kanan maupun dewasa, sehat maupun sakit. Semua orang mempunyai kepantasan diberi hak dan kewajiban, sebab dasar dari kepantasan ini adalah kemanusiaan. Artinya, selama manusia itu masih hidup, kepantasan tersebut tetap dimiliknya, b. Ahliyatul ada’ (kemampuan berbuat)ialah kepantasan seseorang untuk dippandang sah segala perkataan dan perbuatannya. Misalnya, bila mengadakan suatu perjanjian atau perikatan, tindakan itu adalah sah dan dapat menimbulkan akibat hukum, sehingga bersamaan masa datangnya aliyatul dengan tibanya ada’ menurut syara’ adalah usia taqlif yang dibatasi dengan aqil dan baligh. Ahliyatul ada’ terbagi atas dua macam, yaitu: 1. Ahliyatul ada’ sempurna (tam) adalah ketika seorang yang telah berakal mencapai umur dewasa (baligh) dinisbahkan untuk hukum syara’, dan balighnya orang yang cakap dinisbahkan untuk muamallah harta (perdata), 2. Ahliyatul ada’ tidak sempurna (naqish) yaitu anak yang cakap atau semisalnya dinisbahkan untuk muamallah dan perikatan. Adapun taklif syara’ bagi anak yang cakap sama dengan anak yang tidak cakap. Seperti shalatnya anak kecil dianggap seperti orang yang tidak cakap (gila). Sedangkan dalam masalah muamallah dianggap sah jual belinya. Namun demikian, ada beberapa orang yang sudah dewasa dan pantas untuk melaksakan hak dan kewajiban tetapi kondisi mereka tidak memungkinkan untuk melaksanakan semua itu, dikarenakan ada hal-hal yang menghalangi.kondisi tersebut disebut dengan awaridh ahliyah. Ahwaridh ahliyah ada yakni samawiyah dan kasabiyah. 16 dua macam, Samawiyah adalah hal-hal yang berada diluar usaha dan ikhtiar manusia. Halangan samawiyah ada sepuluh macam, yaitu: Keadaan belum dewasa; a. Sakit gila b. Kurang akal c. Keadaan tidur d. Pingsan e. Lupa f. Sakit g. Menstruasi h. Nifas i. Meninggal dunia. Kasabiyah adalah perbuatan-perbuatann yang diusahakan manusia yang menghilangkan atau mengurangi kemampuan bertindak. Halangan kasabiyah itu ada tujuh macam, yaitu: a. Boros, b. Mabuk c. Bepergian d. Lalai e. Bergurau (main-main) f. Bodoh (tidak mengetahui) g. Terpaksa (ikrah). 26 Memperhatikan akibat ahliyatul ada’. Maka gangguangangguan itu terbagi kepada beberapa jenis antara lain: a. Gugur ahliyatul ada’, khusus bagi manusia gila dan sedang tidur. b. Kurang ahliyatul ada’ (tidak gugur seluruhnya), seperti manusia makhluk (orang yang lemah pikirannya) dan juga anak-anak yang mumayiz. c. Tidak menghilangkan dan tidak pula mengurangi ahliyatul ada’, tatpi hanya mengubah kemaslahatan. 26 Ibid., hal. 43-44. 17 sebagian hukum untuk Maka terhadap poin a dan b diatas, tidak dibenarkan memelihara harta, demi untuk memelihara hartanya sedangkan ahliyatnya tetap tidak hilang dan tidak pula berkurang. Dan yang ketiga ahliyatul ada’ nya penuh, hanya tidak dibolehkan mengendalikan hartyanya karena menjaga haknya. 27 Syafi’i Karim, Fiqih-Ushul Fiqih, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), cet. 2, hal. 136. 27 18 BAB III PENUTUP A. KESIMPULAN a. Hukum wadh’i adalah hukum yang bertujuan menjadikan sesuatu adalah sebab untuk sesuatu atau syarat baginya atau penghalang terhadap sesuatu. Adapun yang menjadi bagian dari hukum wadh’i ada 5 yaitu, sebab, syarat, mani’, Ash-Shihah, Al-Buthlan dan Al-Fasad, ‘Azimah dan rukhsah. b. Mahkum Fiih adalah perbuatan-perbuatan orang mukallaf yang dibebani suatu hukum (perbuatan hukum). c. Mahkum ‘alaih ialah orang-orang mukallaf yang dibebani hukum. Adapun syarat-syarat sahnya seorang mukallaf menerima beban hukum itu ada dua macam, yakni: 1. Sanggup memahami khitab-khitab pembebanan atau tuntutan syara’ yang terkandung dalam al-Qur’an dan as-Sunnah, baik secara langsung maupun melalui orang lain. Oleh karena itu, orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memahami khitab syar’i tidak mungkin untuk melaksanakan suatu taklif (pembebanan), 2. Mempunyai kemampuan menerima beban. Dasar pembebanan hukum bagi seorang mukallaf adalah akal dan pemahaman. B. SARAN Dalam era islam masa kini, masih banyak orang yang melanggar dan tidak mengikuti aturan atau hukum yang dibuat Hakim. Padahal hukum sudah jelas tercantum dalam Al-qur’an dan Sunnah Nabi. Manusia sebagai subjek hukum seharusnya dapat mampu menjalankan perbuatan dalam Al-qur’an dan sunnah yang sebagai ojek hukum. Jika Subjek dan Objek hukum tidak berjalan dengan baik, telah dijelaskan dalam hukum akan ada beban hukum yang dibebankan pada manusia itu sendiri. Demikianlah akhir makalah ini. Jika ada penulisan makalah yang kurang tepat kami mohon maaf. Terimakasih kepada pembaca yang telah 19 menyempatkan membaca makalah tentang Hukum Wadh’i, Mahkum Fih, dan Mahkum ‘alaih yang kami buat. Semoga bermanfaat. 20 DAFTAR PUSTAKA A Syafe’i Karim, 1997, Fiqih Ushul Fiqih, Bandung: Pustaka Setia Nasrun Haroen, 1996, Ushul Fiqih I, Jakarta: Pustaka Setia Wahhab Kallaf, Abdul,1994, Ilmu Ushul Fiqih, Semarang: Dina Utama Rachmat Syafe’i, 2010, Ilmu Ushul Fiqih, Bandung: Pustaka Setia Abd. Rahman Dahlan, 2011, Ushul Fiqih, Jakarta: AMZAH http://nalarbumi.blogspot.co.id/2016/01/hukum-wadhi-dan-macam-macamhukum-wadhi.html Hasbiyallah. 2014. Fiqh dan Ushul Fiqh (metode istinbath dan istidlal). Bandung: Remaja Rosdakarya. Cet. Kedua. Umar Muin. Dkk. 1986. ushul fiqh 1. Jakarta: proyek Pembinaan dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN. Umam Khairul. dkk. 2000. Ushul Fiqih 1. Bandung: Pustaka Setia. Cet. Kedua. Karim Syafi’i. 2001. Fiqih-Ushul Fiqih. Bandung: Pustaka Setia. cet. Kedua. 21