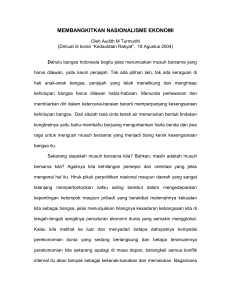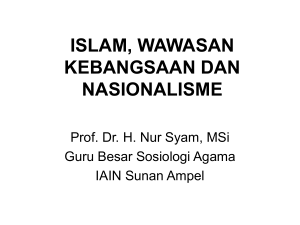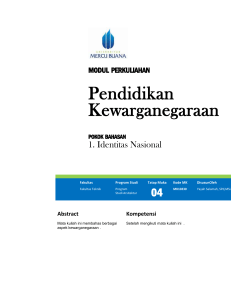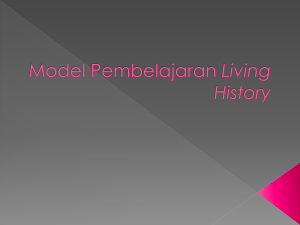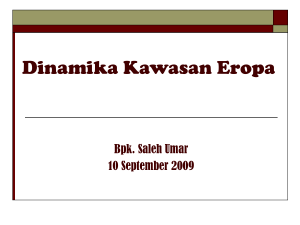Tugas Review Mata Kuliah Dinamika Kawasan Eropa Oleh : Hani
advertisement
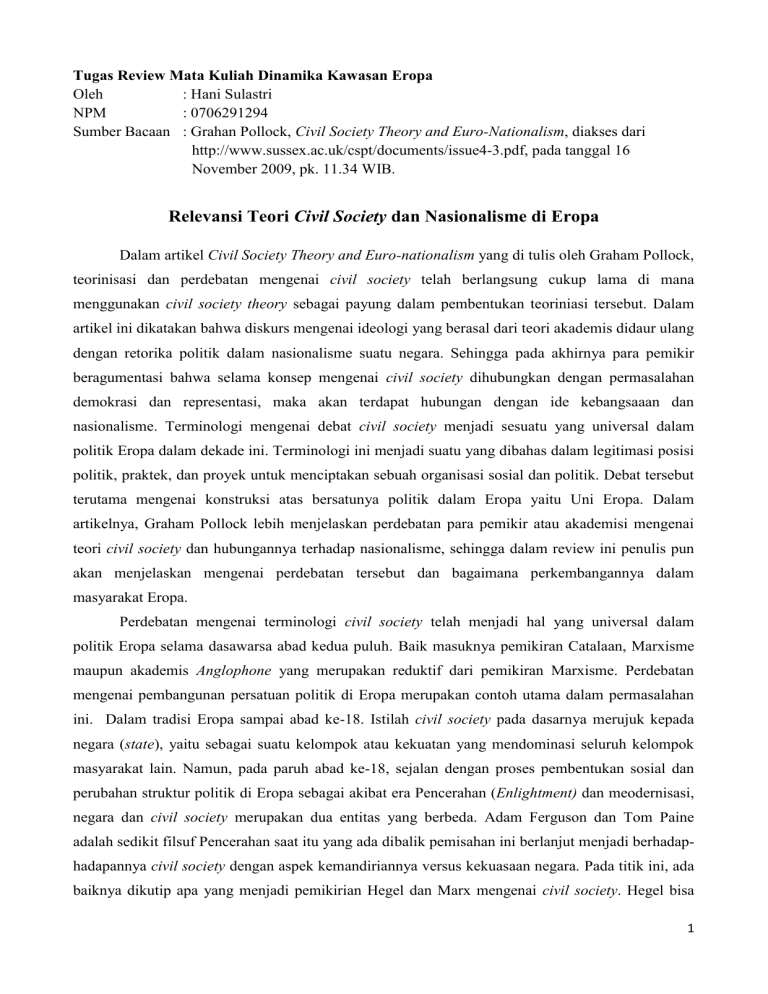
Tugas Review Mata Kuliah Dinamika Kawasan Eropa Oleh : Hani Sulastri NPM : 0706291294 Sumber Bacaan : Grahan Pollock, Civil Society Theory and Euro-Nationalism, diakses dari http://www.sussex.ac.uk/cspt/documents/issue4-3.pdf, pada tanggal 16 November 2009, pk. 11.34 WIB. Relevansi Teori Civil Society dan Nasionalisme di Eropa Dalam artikel Civil Society Theory and Euro-nationalism yang di tulis oleh Graham Pollock, teorinisasi dan perdebatan mengenai civil society telah berlangsung cukup lama di mana menggunakan civil society theory sebagai payung dalam pembentukan teoriniasi tersebut. Dalam artikel ini dikatakan bahwa diskurs mengenai ideologi yang berasal dari teori akademis didaur ulang dengan retorika politik dalam nasionalisme suatu negara. Sehingga pada akhirnya para pemikir beragumentasi bahwa selama konsep mengenai civil society dihubungkan dengan permasalahan demokrasi dan representasi, maka akan terdapat hubungan dengan ide kebangsaaan dan nasionalisme. Terminologi mengenai debat civil society menjadi sesuatu yang universal dalam politik Eropa dalam dekade ini. Terminologi ini menjadi suatu yang dibahas dalam legitimasi posisi politik, praktek, dan proyek untuk menciptakan sebuah organisasi sosial dan politik. Debat tersebut terutama mengenai konstruksi atas bersatunya politik dalam Eropa yaitu Uni Eropa. Dalam artikelnya, Graham Pollock lebih menjelaskan perdebatan para pemikir atau akademisi mengenai teori civil society dan hubungannya terhadap nasionalisme, sehingga dalam review ini penulis pun akan menjelaskan mengenai perdebatan tersebut dan bagaimana perkembangannya dalam masyarakat Eropa. Perdebatan mengenai terminologi civil society telah menjadi hal yang universal dalam politik Eropa selama dasawarsa abad kedua puluh. Baik masuknya pemikiran Catalaan, Marxisme maupun akademis Anglophone yang merupakan reduktif dari pemikiran Marxisme. Perdebatan mengenai pembangunan persatuan politik di Eropa merupakan contoh utama dalam permasalahan ini. Dalam tradisi Eropa sampai abad ke-18. Istilah civil society pada dasarnya merujuk kepada negara (state), yaitu sebagai suatu kelompok atau kekuatan yang mendominasi seluruh kelompok masyarakat lain. Namun, pada paruh abad ke-18, sejalan dengan proses pembentukan sosial dan perubahan struktur politik di Eropa sebagai akibat era Pencerahan (Enlightment) dan meodernisasi, negara dan civil society merupakan dua entitas yang berbeda. Adam Ferguson dan Tom Paine adalah sedikit filsuf Pencerahan saat itu yang ada dibalik pemisahan ini berlanjut menjadi berhadaphadapannya civil society dengan aspek kemandiriannya versus kekuasaan negara. Pada titik ini, ada baiknya dikutip apa yang menjadi pemikirian Hegel dan Marx mengenai civil society. Hegel bisa 1 dibilang filsuf Jerman yang mulai melakukan pembedaan antara negara dan civil society. Menurutnya, civil society adalah wilayah kehidupan orang-orang yang telah meninggalkan kesatuan keluarga dan masuk kedalam kehidupan ekonomi yang kompetitif. Ia adalah burgerliche Gesellschaft atau masyarakat Borjuis yang berada diantara keluarga dan negara yang terssun dari unsur-unsur keluarga, korporasi atau asosiasi, dan aparat administrasi atau legal. Ia adalah (political order) secara keseluruhan. Sementara itu tatanan politik yang lain adalah negara (state) atau masyarakat politik (political society). Munculnya kuasi hegemonik mengenai perubahan sosial dan politik dalam sistem negara menimbulkan pertanyaan mengenai prosedur sistem demokrasi. Transparasi hubungan antara policy maker dan masyarakat yang diwakili, menjadi hal yang penting dalam wacana pelaksaan demokrasi didalam pembentukan bersatunya Eropa. Hal ini menjadikan akademisi cenderung menjadi penasehat bagi pemerintah di Eropa sehingga jarak antara wacana akademisi dan praktek politik telah menjadi wilayah sekunder dalam teorinisasi. Dalam perjalanannya, teori civil society mulai dihubungkan dengan nasionalisme. Dahulu teori civil society menjadi sebuah dokrtin non-interfensi dengan partai politik dan membenarkan secara diam-diam keadaan status quo. Namun, pascanasionalisme, terdapat gerakan-gerakan nasionalisme di mana masyarakat sipil mulai berbicara dalam perpolitikan Eropa, hal ini terlihat pada saat Revolusi Industri dan Revolusi Perancis. Sikap kritis gerakan nasionalis untuk mendirikan sebuah negara menjadi retorika dari sebuah negara yang nasionalismenya dangkal. Praktik politik ini adalah sebuah nasionalisme dangkal suatu negara yang ditutupi oleh retorika munafik anti nasionalis yang digunakan oleh negara terhadap kaum minoritas yang kemudian dicap sebagai kaum nasionalis, sementara pada tingkat teoritis, hal tersebut dikaburkan oleh teori masyarakat sipil yang implisit merupakan metodologis individualisme dengan asumsi bahwa bangsa-bangsa diciptakan oleh nasionalisme. Anderson menawarkan pandangan yang lebih positif tentang nasionalisme, ia menyatakan bahwa bangsa atau nation adalah komunitas politis dan dibayangkan (imagined) sebagai sesuatu yang bersifat terbatas secara inheren sekaligus berkedaulatan.1 Lebih jauh dia memaparkan bahwa bangsa disebut komunitas karena ia sendiri selalu dipahami sebagai kesetiakawanan yang masukmendalam dan melebar-mendatar, sekalipun ketidakadilan dan penghisapan hampir selalu ada dalam setiap bangsa. Bangsa disebut sebagai komunitas terbayang (imagined community) karena para anggota bangsa terkecil tidak mengenal sebagian besar anggota lain, bahkan mungkin tidak pernah mendengar tentang mereka. Ia dibayangkan sebagai sesuatu yang terbatas karena bangsabangsa yang paling besar sekalipun memiliki garis-garis batas yang pasti dan jelas meski terkadang 1 Benedict Anderson, Imagined Community: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism, (London: Verso, 1991), hal. 56-64. 2 bersifat elastis. Di luar garis batas itu adalah bangsa lain yang berbeda dengan mereka. 2 Dalam sejarah, nasionalisme bermula dari benua Eropa sekitar abad pertengahan. Kesadaran berbangsa — dalam pengertian nation-state— dipicu oleh gerakan Reformasi Protestan yang dipelopori oleh Martin Luther di Jerman.3 Saat itu, Luther yang menentang Gereja Katolik Roma menerjemahkan Perjanjian Baru kedalam bahasa Jerman dengan menggunakan gaya bahasa yang memukau dan kemudian merangsang rasa kebangsaan Jerman. Terjemahan Injil membuka luas penafsiran pribadi yang sebelumnya merupakan hak eksklusif bagi mereka yang menguasai bahasa Latin, seperti para pastor, uskup, dan kardinal. Implikasi yang sedikit demi sedikit muncul adalah kesadaran tentang bangsa dan kebangsaan yang memiliki identitas sendiri. Bahasa Jerman yang digunakan Luther untuk menerjemahkan Injil mengurangi dan secara bertahap menghilangkan pengaruh bahasa Latin yang saat itu merupakan bahasa ilmiah dari kesadaran masyarakat Jerman. Mesin cetak yang ditemukan oleh Johann Gothenberg turut mempercepat penyebaran kesadaran bangsa dan kebangsaan. Namun demikian, nasionalisme Eropa yang pada akhirnya menghasilkan deklarasi hak-hak manusia berubah menjadi kebijakan yang didasarkan atas kekuatan dan self interest dan bukan atas kemanusiaan. Dalam perkembangannya nasionalisme Eropa berpindah haluan menjadi persaingan fanatisme nasional antar bangsa-bangsa Eropa yang melahirkan penjajahan terhadap negeri-negeri yang saat itu belum memiliki identitas kebangsaan (nasionalisme) di benua Asia, Afrika, dan Amerika Latin.4 Fakta ini merujuk pada dua hal: (1) ledakan ekonomi Eropa pada masa itu yang berakibat pada melimpahnya hasil produksi dan (2) pandangan pemikir Italia, Nicolo Machiaveli, yang menganjurkan seorang penguasa untuk melakukan apapun demi menjaga eksistensi kekuasaannya. Dia menulis: “Bila ini merupakan masalah yang mutlak mengenai kesejahteraan bangsa kita,maka janganlah kita menghiraukan keadilan atau ketidakadilan, kerahiman dan ketidakrahiman, pujian atau penghinaan, akan tetapi dengan menyisihkan semuanya menggunakan siasat apa saja yang menyelamatkan dan memelihara hidup negara kita itu”.5 Nasionalisme yang pada awalnya mementingkan hak-hak asasi manusia pada tahap selanjutnya menganggap kekuasaan kolektif yang terwujud dalam negara lebih penting daripada kemerdekaan individual. Pandangan yang menjadikan negara sebagai pusat merupakan pandangan beberapa beberapa pemikir Eropa saat itu, diantaranya Hegel. Dia berpendapat bahwa kepentingan negara didahulukan dalam hubungan negara-masyarakat, karena ia merupakan kepentingan obyektif sementara kepentingan masing-masing individu adalah kepentingan subyektif. Negara adalah ideal 2 Ibid. hal 74-76 Michael Edwards, Civil Society. (Cambridge: Polity Press, 2004 ), hal 43-45. 4 Hans Kohn, The Idea of Nationalism: A Study in Its Origins andBbackground, (New York: Macmillan, 1971), hal. 123. 5 Ibid. hal. 126. 3 3 (geist) yang diobyektifikasi, dan karenanya, individu hanya dapat menjadi sesuatu yang obyektif melalui keanggotaannya dalam negara. Lebih jauh dia menyatakan bahwa negara memegang monopoli untuk menentukan apa yang benar dan salah mengenai hakikat negara, menentukan apa yang moral dan yang bukan moral, serta apa yang baik dan apa yang destruktif.6 Hal ini melahirkan kecenderungan nasionalisme yang terlalu mementingkan tanah air (patriotisme yang mengarah pada chauvinisme), yang mendorong masyarakat Eropa melakukan ekspansi-ekspansi ke wilayah dunia lain. Absolutisme negara dihadapan rakyat memungkinkan adanya pemimpin totaliter, yang merupakan bentuk ideal negara yang dicitakan Hegel, sebuah monarki.7 Totaliterianisme yang dianjurkan oleh filsafat negara Hegel dapat menggiring sebuah pemerintahan menjadi pemerintahan yang fasis. Fasisme adalah doktrin yang mengajarkan kepatuhan mutlak terhadap perintah dalam semua aspek kehidupan nasional. Dalam sejarahnya, fasisme terkait erat dengan rasisme yang mengunggulkan sebagian ras (suku) atas sebagian yang lain. Menurut Hugh Purcell nasionalisme dan rasisme merupakan gambaran paling terkenal dari fasisme pada tahun 1930-an.8 Rasisme memiliki kaitan erat dengan nasionalisme. Keduanya berbeda pada penekanan. Rasisme menekankan superioritas suku dan nasionalisme menekankan keunggulan bangsa (komunitas terbayang yang lebih besar dari suku). Manusia nasionalis adalah seseorang dengan kebanggaan terhadap bangsanya yang kadang diungkapkan dengan cara berlebihan. Nasionalisme dan rasisme memiliki keserupaan dalam hal pengunggulan dan kebanggaan terhadap sesuatu yang secara alamiah melekat pada setiap manusia. Yang pertama kebanggaan terhadap bangsa—sistem pemerintahan, suku, dan budaya. Yang kedua kebanggaan terhadap suku. Dalam tulisan ini penulis melihat terdapa dua sebab mengapa dari waktu ke waktu masalah nasionalisme selalu timbul ke permukaan, yaitu obyektif-historis dan subyektif historis di mana kedua sisi historis ini tidak terpisah satu dengan yang lainnya. Nasionalisme adalah tipikal gejala zaman modern, yakni ketika dinamika Revolusi Industri pada pertengahan abad ke-19 mulai merentangkan lilitannya ke seantreo benua, membagi wilayah-wilayah politik dan ekonomi. Pembagian wilayah-wilayah ini antara lain dipermudah oleh sejumlah penaklukan militer oleh bangsa-bangsa Eropa sejak beberapa abad sebelumnya berkat revolusi di bisang navigasi serta temuan-temuan rute pintas dunia. Inilah yang disebut sebagai obyektif historis. Revolusi Industri bukan hanya mengubah batas-batas negara di senatreo dunia. Jauh lebih penting, ia telah mengubah tempo dari berlangsungnya perubahan batas-batas negara dan menetaskan berbagai dimensi baru dalam kehidupan politik. Sebagaimana ia meningkatkan tempo dalam pertarungan ekonomi antarbangsa, ia pun meningkatkan tempo dalam pertarungan politik antar-bangsa dan di dalam masing6 Marsillam Simandjuntak, Pandangan Negara Integralistik: Sumber, Unsur, dan Riwayatnya Dalam Persiapan UUD 1945, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2003), hal. 166. 7 Ibid., hal. 224. 8 Hugh Purcell, Fascism, (Melbourne : Nelson, 1981), hal. 11. 4 masing bangsa. Hal inilah yang menjawab pertanyaan mengapa negara-negara Eropa disaat nasionalismenya bangkit pada saat revolusi, ia menjajah bangsa-bangsa di luar Eropa. Atas nama natie, bangsa-bangsa Eropa menjajah Asia dan Afrika untuk pertarungan ekonomi dan pertarungan politik antar-bangsa Eropa. Sebab kedua mengapa kita tidak mungkin mengelak dari masalah nasionalisme bersifat subyektif historis adalah kerangka ini kita harus menyimak kembali gagasan Ernest Renan dalam karyanya yaitu “What is a Nation” di mana Renan mengatakan: “Bangsa adalah suatu solidaritas luhur, yang terbina dari penghayatan akan pengorbanan yang telah diberikan oleh para warganya, dan kesiapan mereka untuk tetap melakukan pengorbananpengorbanan.”9 Karena itu, dalam tinjauan Renan, bangsa tidak terutama ditentukan oleh ras, agama, bahasa, ataupun tanah air, meskipun keempat-empatnya penting. Penulis merumuskan kembali pandangan Renan yaitu bangsa bertumpu pada rangkuman pengalaman-pengalaman bermakna yang telah dialami bersama untuk menghadapi segenap tantangan di masa depan. Dari sinilah lahirnya katakata Renan yang tetap bergema hingga sekarang ‘Bangsa adalah suatu nafas yang hidup, suatu prinsip spiritual’. Internalisasi dari pengalaman-pengalaman bermakna dari masa lampu dan kesiapan untuk mengulanginya itulah yang disebut sebagai sisi subyektif historis nasionalisme. Pada akhirnya penulis melihat bahwa teori civil society yang mulai melakukan pendekatan terhadap politik dalam hal ini negara maka akan semakin berhubungan terhadap nasionalisme suatu bangsa. Dalam artikel ini nasionalisme dianggap suatu hal yang negatif karena menekankan kepada perbedaan budaya dan memiliki kecenderungan ke arah rasisme, sedangkan patriotisme menjadi kekuatan kohesif di mana patriotisme konstitusional membela gagasan kewarganegaraan kosmopolitan yang mengacu pada pendapat minimum bahwa budaya adalah unsur-unsur opsional ekstra yang tidak terdapat dalam pemilihan terakhir di parlemen Eropa. Patriotisme konstitusional sebenarnya merupakan pendekatan idealis nasionalisme tanpa bangsa. Ini adalah bagian dari retorika ideologi teori masyarakat sipil yang digunakan untuk melegitimasi suatu bentuk homogenisasi kewarganegaraan dan absolutisme hukum dari didrikannya suatu negara. Pendukung ‘negara-negara Eropa’ berpendapat bahwa European Union merupakan sebuah pertemuan negaranegara Eropa bukanlah penyatuan warga dan bangsa yang sebagai sebuah mosail yang penuh warna dan mensyaratkan masing-masing potongan sama-sama dihormati. Pilihan yang mudah untuk menciptakan European Unioun lebih baik menggunakan jalan secara politis yang bersifat top down seperti yang diutarakan dalam artikel Civil Society Theory and Euro-Nationalism, karena penyatuan ini berdasarkan pada gerakan-gerakan politik yang terjadi di masyarakat Eropa. Ernst Renan, What’s a nation, diakses dari http://ig.cs.tuberlin.de/oldstatic/w2001/eu1/dokumente/Basistexte/Renan1882EN-Nation.pdf, pada tanggal 20 November 2009, pk. 11.27 WIB. 9 5