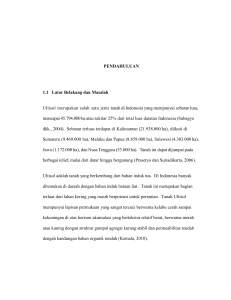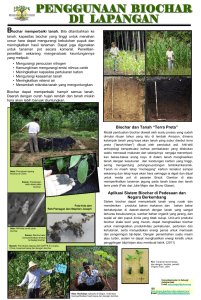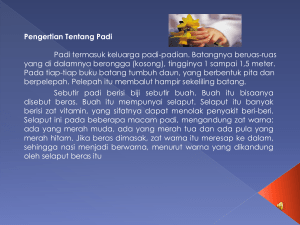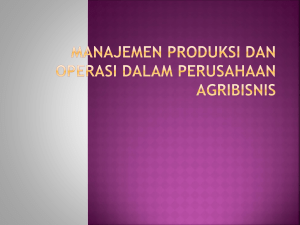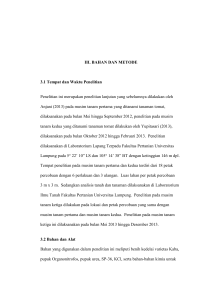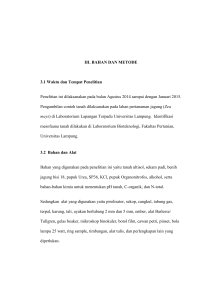Perubahan Sifat Fisika Ultisol Akibat Pembenah Tanah dan Pola
advertisement

Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana (SNP) Unsyiah 2017, April 13, 2017, Banda Aceh, Indonesia Perubahan Sifat Fisika Ultisol Akibat Pembenah Tanah dan Pola Tanam Andi A Muhidin, *Darusman, Manfarizah Jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh, 23111, Indonesia *Corresponding Author: [email protected] Abstrak Ultisol adalah salah satu jenis tanah yang banyak dijumpai pada daerah daerah yang mempunyai curah hujan tinggi dengan tingat pelapukan yang intensif dan tingkat pemcucian yang aktif. Ultisol dikatagorikan tanah bermasalah (problem soils) karena sifat tanah nya masam dan unsur hara yang rendah sehingga diperlukan pengelolaan tanah yang sangat hati hati. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dampak pemberian beberapa pembenah tanah dan pola tanam terhadap sifat fisika tanah sehingga remediasi ultisol bisa dengan mudah diterapkan. Penelitian dilaksanakan di Gampong Teureubeh, jantho yang berketinggian 100 m dpl. Curah hujan rata rata 2200 mm setiap tahunnya dengan bulan basah 4-6 dan bulan kering 2-4 bulan. Penelitian menggunakan rancangan acak kelompok factorial dengan 5 perlakuan yang diulang 3 kali. Faktor pembenah tanah terdiri dari NPK 0.4 t ha -1, biochar 10 t ha, pupuk kandang 10 t ha-1, biochar 10 t ha-1 + 0.4 t ha-1 dan pupuk kandang 10 t ha-1 plus NPT 0.4 t ha-1. Sedangkan faktor kedua adalah pola tanam yang terdiri dari mono culture jagung, monokullture kedelai dan tumpang sari jagungkedelai. Parameter yang diamati adalah berat volume tanah, porositas tanah, kadar air pada pF 2.54 dan 4.2, permeabilitas tanah serta indeks stabilitas aggregate tanah. Hasil peneltian menunjukkan bahwa pembenah tanah dan pola tanam memberikan efek yang sama yaitu tidak memberikan pengaruh nyata terhadap berat volume tanah, porositas tanah, kadar air tanah pada pf 2.54 dan 4.2, permeabilitas tanah serta indeks stabilitas aggregate tanah. Tidak terdapat interaksi antara perlakuan pembenah tanah pola dan tanam terhadap semua peubah sifat fisika tanah kecuali permeabilitas tanah pada dua kedalaman yaitu top dan sub soil. Kata kunci: utisol, tanah, pola tanam. Pendahuluan Lahan kering (dryland) umumnya terdapat didataran tinggi (daerah pengunungan) yang ditandai dengan topografi yang bergelombang dan merupakan daerah penerima dan peresap air hujan yang kemudian dialirkan kedataran rendah, baik melalui daerah aliran sungai (DAS) maupun struktur geologi tanah. Jadi lahan kering didefinisikan sebagai dataran tinggi yang lahan pertaniannya lebih banyak curah hujan seperti tanah masam Ultisol (Hasnudi dan Eniza, 2004). Salah satu jenis tanah yang banyak terdapat di lahan kering adalah Ortosol. Tanah ordo Ultisol merupakan salah satu jenis tanah yang dijumpai di Indonesia yang penyebarannya di beberapa pulau besar mencapai luas sekitar 45.794.000 ha atau 25% dari luas wilayah daratan Indonesia, dan termasuk ordo tanah yang luas di bandingkan dengan tanah yang lain. Tanah ini berkembang pada berbagai topografi, mulai dari A120 Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana (SNP) Unsyiah 2017, April 13, 2017, Banda Aceh, Indonesia bergelombang hingga bergunung dengan curah hujan yang tinggi (Subagyo et al., 2004). Berdasarkan luas ultisol mempunyai potensi yang tinggi untuk pengembangan pertanian lahan kering. Namun demikian, pemanfaatan tanah ini terdapat kendala pada sifat fisika tanah yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman, terutama tanaman pangan seperti kedelai dan jagung bila tidak dikelola dengan baik. Menurut hasil penelitian Sutedjo dan kartasapoetra (1991) perbaikan sifat fisika tanah mutlak diperlukan pada tanah Ultisol agar dapat mempertahankan kondisi tanah yang baik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan penambahan bahan pembenah tanah seperti biochar, pupuk kandang sapi dan pupuk NPK ke dalam tanah yang bertujuan untuk memperbaiki sifat-sifat tanah secara simultan. Pembenah tanah yang sangat banyak digunakan selama ini adalah biochar. Biochar adalah arang hayati dan mampu menangkap karbon di udara dan menyimpannya bertahun tahun (Kuzyakov et al., 2009). Dibandingkan dengan pupuk kandang, maka biochar lebih aman dan sudah diakui sebagai Carbon Management (Sohi et al., 2010). Umunya didalam tanah bahan pembenah tanah digunakan untuk pemantap agregat tanah karena mengandung carbon (organic matter) sebagai pemantap aggregat tanah. Oleh karena itu pembenah tanah juga berfungsi mengurangi resiko erosi, meningkatkan kapasitas tanah menahan air (water holding capacity) karena bahan ini memiliki sifat yang mampu merubah sifat hidrofobik atau hidrofilik dan mampu meningkatkan kapasitas tukar kation (KTK) tanah (Arsyad, 2000). Biochar atau arang merupakan bahan pembenah tanah alami berbahan baku hasil pembakaran tidak sempurna (pyrolisis) dari residu atau limbah pertanian yang sulit didekomposisi, seperti kayu-kayuan, sekam padi, dan lain-lain. Pembakaran tidak sempurna dilakukan pada suhu sekitar 250-350°C, selama 2-3,5 jam sehingga diperoleh arang yang mengandung karbon tinggi dan dapat diaplikasikan untuk memperbaiki struktur tanah (Lehmann and Rondon, 2006). Pada tanah Ultisol, Pemberian biochar dengan takaran 6 t per hektar dapat meningkatkan karbon, bahan organik dan rasio CN yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman jagung (Latuponu, 2010). Bahan organik tanah menjadi salah satu indikator penting dalam memperbaiki kesehatan tanah karena memiliki beberapa peranan kunci di tanah, disamping itu bahan organik tanah memiliki fungsi yang saling berkaitan, sebagai contoh bahan organik tanah menyediakan nutrisi untuk aktifitas mikroba yang juga dapat meningkatkan dekomposisi bahan organik, meningkatkan stabilitas agregat tanah, dan meningkatkan daya pulih tanah (Sutanto, 2005). Bahan organik tanah memiliki peran dan fungsi yang sangat vital di dalam perbaikan sifatsifat tanah yang meliputi sifat fisika, kimia dan biologi tanah. Bahan organik merupakan sumber energi bagi aktivitas mikrobia tanah dan dapat memperbaiki berat volume tanah, struktur tanah, aerasi serta daya mengikat air (Marzuki et al., 2012). Hal ini sejalan dengan pendapat Erfandi dan Juarsah (2004) yang menyatakan bahwa pemberian bahan organik pada tanah ordo Ultisol dapat memperbaiki kadar air tersedia dalam tanah, menurunkan berat volume tanah dan pori aerasi serta indeks stabilitas agregat top soil (0-20 cm). Tisdale dan Nelson (1975) menyebutkan bahwa pupuk kandang merupakan komponen penting dalam mengelola tanah masam seperti Ultisol. Pemberian pupuk kandang dapat memperbaiki struktur dan granulasi tanah, meningkatkan daya menahan air, serta memperbaiki permeabilitas tanah. Pemberian pupuk kandang sapi dapat memperbaiki sifat fisik tanah, seperti meningkatkan porositas tanah dan laju permeabilitas (Adimihardja dan Kurnia., 2000). Mereka juga menyatakan bahwa pemberian pukan sapi, dengan takaran 5 t ha-1 pada tanah Ultisol Jambi nyata meningkatkan kadar C-organik tanah, dan hasil jagung dan kedelai. Wiskandar (2002) melaporkan penggunaan pupuk kandang sapi 20 t ha-1 mampu memberikan hasil biji 1,21 t ha-1 pada tanaman kedelai. Pemberian pukan 5 t ha-1 dikombinasikan dengan pemupukan NPK (90-45-80) pada tanaman jagung pada lahan A121 Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana (SNP) Unsyiah 2017, April 13, 2017, Banda Aceh, Indonesia kering masam dapat memberikan hasil biji pipilan 3,4 t ha-1, yaitu 1,9 t ha-1 lebih tinggi dari pemupukan NPK saja (Adiningsih et al., 1995). Disamping itu pupuk NPK merupakan unsur hara makro yang mutlak diperlukan tanaman selama proses pertumbuhannya. Dosis pupuk NPK phonska yang digunakan untuk meningkatkan produktifitas kedelai 250 kg ha-1 yang dibagi dua tahap pemberian, 125 kg ha-1 pada saat tanam dan 125 kg ha-1 untuk 30 Hari setelah tanam (PT. Petrokimia Gresik, 2012). Jeffery et al. (2011) menemukan bahwa Biochar meningkatkan secara nyata produktivitas tanaman radishes dan soybeans, sebaliknya untuk tanaman rye-grass. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perbaikan sifat-sifat fisik tanah akibat pembenah tanahi biochar dan pupuk organik akan meningkatnya persentase partikel tanah yang berbentuk agregat (Suwardjo et al., 1989). Namun, referensi jenis pembenah yang mana lebih efektif dan responnya terhadap sifat sifat tanah serta produktivitas tanaman masih relative sedikit. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu diteliti bagaimana respon sifat fisika tanah akibat pemberian NPK, Biochar dan pupuk kandang serta kombinasinya. Bahan dan Metode Penelitian ini dilakukan di Gampong Teureubeh, Mukim Jantho, Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar. Gampong Teureubeh terletak pada titik kordinat 05°17’05.2” LU dan 95°35’12.1” BT. Topografi kawasan kota Jantho datar, bergelombang hingga berbukit-bukit. Kota Jantho memiliki ketinggian 100 dpl, Gampong Teureubeh memiliki temperatur sekitar 22-35°C atau rata-rata 26.7°C dengan curah hujan tahunan 2.200 mm dengan jumlah bulan basah 4-6 bulan dan bulan kering 2-4 bulan. Lahan ini adalah lahan produksi yang pernah ditanami tanaman semusim seperti jagung, kacang panjang, oleh petani. Sebelum ditanami tanaman semusim terlebih dahulu di analisis sifat-sifat Fisika di Laboratorium Penelitian Fisika Tanah dan Lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala dan pembuatan bahan pembenah tanah (Biochar) dilakukan di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh. Penelitian ini berlangsung dari bulan Juni-Oktober 2016. Bahan yang digunakan adalah pembenah tanah biochar arang sekam 7,35 kg, pupuk kandang sapi 7,35 kg dan pupuk NPK 294 gram per bedeng, (hanya bedeng yang di anjurkan) sebagai perlakuan, dan benih tanaman jagung varietas Bonanza dan kedelai Varietas Dena 1. Alat alat yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu GPS (Global Positioning System) untuk menentukan posisi di lapangan, kamera digital, alat tulis, cangkul, bor tanah, meteran, ring sampel tanah, kantg plastik, dan alat-alat laboratorium untuk analisis sifat fisika tanah yaitu : pisau lapang, pengaris ukur, karet gelang, kertas label, eksikator, oven, timbangan analitik, cawan aluminium, kertas saring, keramik plate, pressure plate/membrane plate apparatus, permeameter, stopwatch. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan pola faktorial 5 x 3 dengan 3 ulangan. Adapun faktor yang diteliti yaitu pembenah tanah (A) dan pola tanam (S). Faktor pertama adalah pembenah tanah A0 = NPK 0.4 t A1 = Biochar 10 t ha-1 A2 = Pupuk kandang 10 t ha-1 A3 = Biochar 10 t ha-1 + NPK 0.4 t A4 = Pupuk kandang 10 t ha-1 + NPK 0.4 t Faktor kedua adalah pola tanam S1 = Monokultur Jagung S2 = Monokultur Kedelai S3 = Tumpang Sari Jagung-Kedelai A122 Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana (SNP) Unsyiah 2017, April 13, 2017, Banda Aceh, Indonesia Dengan demikian terdapat 15 kombinasi perlakuan dengan 3 ulangan. Maka jumlah satuan kombinasi perlakuan adalah 45 satuan percobaan. Tabel 1. Kombinasi Perlakuan No Kombinasi Perlakuan Pembenah Tanah 1 A0S1 NPK 0.4 t Monokultur Jagung 2 A0S2 NPK 0.4 t 3 A0S3 NPK 0.4 t 4 5 A1S1 A1S2 biochar 10 t ha-1 biochar 10 t ha-1 6 A1S3 biochar 10 t ha-1 7 A2S1 Pupuk kandang 10 t ha-1 Monokultur Kedelai Tumpang Sari JagungKedelai Monokultur Jagung Monokultur Kedelai Tumpang Sari JagungKedelai Monokultur Jagung 8 A2S2 Pupuk kandang 10 t ha-1 Monokultur Kedelai 9 A2S3 Pupuk kandang 10 t ha-1 Tumpang Sari JagungKedelai 10 A3S1 Biochar 10 t ha-1+ NPK 0.4 t Monokultur Jagung 11 A3S2 Biochar 10 t ha-1+ NPK 0.4 t Monokultur Kedelai 12 A3S3 Biochar 10 t ha-1+ NPK 0.4 t 13 A4S1 Pupuk kandang 10 t ha-1+ NPK 0.4 t Tumpang Sari JagungKedelai Monokultur Jagung 14 A4S2 Pupuk kandang 10 t ha-1 + NPK 0.4 t Monokultur Kedelai 15 A4S3 Pupuk kandang 10 t ha-1 + NPK 0.4 t Tumpang Sari JagungKedelai Sistem Pertanaman Pelaksanaan Penelitian Sebelum diberikan perlakuan terlebih dahulu dilakukan analisis awal sifat-sifat fisika tanah. Sampel tanah diambil pada tiga titik dalam luasan lahan dan tanah di ambil bagian top soil pada kedalaman 0-20 cm dan sub soil pada kedalaman 20-40 cm dan diberi label. Analisis sifat fisika tanah yang dilakukan meliputi penetapan berat volume tanah (bulk density), penetapan porositas tanah, penetapan particle density, penetapan kandungan air tanah, penetapan permeabilitas tanah, penetapan indeks stabilitas agregat. Sedangkan analisis tanah akhir dilakukan setelah panen. Pengambilan sampel tanah utuh dilakukan untuk menentukan penetapan berat volume tanah, penetapan porositas tanah, penetapan particle density tanah, penetapan kandungan air tanah, penetapan permeabilitas tanah, penetapan indeks stabilitas agregat tanah. Analisis tanah dilakukan dengan mengambil sampel tanah secara ring sample sehingga dapat mewakili dari lokasi tersebut. Teknis pengambilan sampel tanah dilakukan tiga titik dalam luasan lahan, dan tanah di ambil bagian top soil pada kedalaman 0-20 cm dan sub soil pada kedalaman 20-40 cm dan diberi label. Pengambilan sampel tanah dilakukan sebanyak 2 kali yaitu sebelum pemberian pembenah tanah dan sehari sebelum panen tanaman jagung dan kedelai dengan tidak merusak titik tanah yang mau diambil untuk pengambilan sampel terakhir. Persiapan Lahan dan Penanaman A123 Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana (SNP) Unsyiah 2017, April 13, 2017, Banda Aceh, Indonesia Lahan yang digunakan pada penelitian ini adalah lahan dengan jenis tanah Ultisol di Gampong Teureubeh, Mukim Jantho, Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar. Lahan dibagi menjadi tiga blok dengan jarak antar blok 1 meter. Setiap blok dibagi atas 15 plot dengan ukuran per plot adalah 3,5 x 2,1 meter, jarak antar plot dalam blok 70 cm. Susunan plot disesuaikan dengan perlakuan, setelah tanah diolah sebanyak dua kali lalu diberikan pembenah tanah sesuai perlakuan dan diinkubasi selama satu minggu. Sebagai tanaman indikator ditanami jagung dan kedelai. Setiap lubang tanam diisi 3 benih dengan kedalaman 3-5 cm lalu ditutup dengan tanah. Pada sistem tanam monokultur jagung, benih jagung ditanam kedalam lubang tanam dengan jarak tanam 75 cm antar jalur dan 30 cm dalam jalur. Pada sistem tanaman monokultur kedelai, biji kedelai ditanam kedalam lubang dengan jarak tanam 30 cm dalam jalur dan 30 cm antar jalur. Pada sistem tumpang sari, kedelai ditanam terlebih dahulu setelah 25 hari baru dilakukan penanaman jagung dengan pola tanaman1 jalur jagung diselingi dengan 4 jalur kedelai dengan jarak antara jagung ke kedelai 30 cm dan 30 cm antar jalur jagung serta 30 cm antar jalur kedelai. Penyiraman dilakukan bila tidak hujan untuk mempertahankan ketersediaan air bagi tanaman Pupuk yang digunakan adalah pupuk kandang sapi, biochar arang sekam, dan NPK. Masingmasing sebanyak, 10 t pupuk kandang sapi ha-1 atau 7,35 kg per bedeng, 10 t ha-1 biochar atau 7,35 kg per bedeng, dan NPK 0.4 t atau 294 g per bedeng. (hanya bedeng yang dianjurkan). Pemupukan pupuk kandang sapi dan biochar arang sekam dilakukan 1 minggu sebelum penanaman dan pemberian pupuk NPK diberikan tiga tahap, pemupukan pertama diberikan sebelum penanaman kedelai, pemupukan kedua diberikan 3 minggu setelah penanaman kedelai, pemupukan ketiga diberikan 3 minggu setelah penanaman jagung. Pengamatan Pengamatan perubahan sifat fisika tanah yang dilakukan meliputi: berat volume tanah, porositas tanah, particel density tanah, kandungan air tanah, permeabilitas tanah, indeks stabilitas agregat tanah. Tabel 2. Parameter dan Metode Analisis Sifat Fisika Tanah 1. 2. 3. 4. 5. 6. Aspek analisis Berat volume Tanah Partikel Density Tanah Porositas Tanah Kadar air tanah pada beberap pF Permeabilitas Tanah Indeks Stabilitas Agregat Tanah Metode Ring Sampel (Core Method) Ring Sampel Ring Sampel (Pengukuran Kadar Air) Pressure Plate Penggenangan (Permeameter) Pengayakan Kering dan Basah Hasil dan Pembahasan Berat volume dan Porositas Hasil analisis ragam (ANOVA) menunjukkan bahwa pemberian bahan pembenah tanah dan pola tanaman terhadap berat volume tanah dan positas tanah top soil dan sub soil tidak berpengaruh nyata. Kadar Air Tanah pada pF 2,54 dan pF 4,2 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pemberian bahan pembenah tanah pada kedalaman top soil tidak berpengaruh nyata pada kadar air tanah pada pF 2,54 dan pF 4,2. A124 Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana (SNP) Unsyiah 2017, April 13, 2017, Banda Aceh, Indonesia Tabel 3. Rata - Rata Nilai Kadar Air Tanah Pada pF 2,54 dan pF 4,2 Akibat Pemberian Bahan Pembenah Tanah Kadar Air Tanah (%) Kadar Air Perlakuan pF 2,54 pF 4,2 Tersedia (%) 0-20 0-20 Bahan Pembenah Tanah 32,45 17,55 14,90 A0 NPK 0.4 t -1 32,78 17,57 15,21 A1 Biochar 10 t ha 32,53 17,63 14,90 A2 Pukan 10 t ha-1 -1 33,27 18,37 14,90 A3 Biochar 10 t ha + NPK 0.4 t 32,82 17,92 14,90 A4 Pukan 10 t ha-1 + NPK 0.4 t BNT 0,05 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pemberian bahan pembenah tanah pada berbagai kedalaman tanah tidak berpengaruh nyata pada kadar air tanah pada pF 2,54 dan pF 4,2. Pola tanam hanya berpengaruh pada kadar air tanah pF4.2 pada kedalaman sub soil. Tabel 4. Rata - Rata Nilai Kadar Air Tanah Pada pF 2,54 dan pF 4,2 Akibat Perlakuan Pola Tanam Kadar Air Tanah (%) Kadar Air Perlakuan pF 2,54 pF 4,2 Tersedia (%) 0-20 0-20 Pola Tanam S1 Monokultur Jagung S2 Monokultur Kedelai S3 Tumpang Sari Jagung Kedelai BNT 0,05 33,16 32,38 32,77 - 18,26 b 17,29 a 17,87 ab 0,66 14,90 15,09 14,90 Keterangan : Angka - Angka yang Diikuti Huruf yang Sama pada Kolom Sama Tidak Berbeda Nyata Menurut Uji BNT 0,05 Tabel 4 menunjukkan bahwa pada kedalaman top soil persentase kadar air tanah pF 4,2 tertinggi dijumpai pada perlakuan S1 (Monokultur Jagung) yakni 18,26 % dan terendah dijumpai pada S2 (Monokultur Kedelai) yakni 17,29 %. yang berbeda nyata dengan perlakuan pola tanam lainnya, kecuali pada perlakuan S3 (Tumpang Sari Jagung Kedelai) yakni 17,87 %. Sedangkan air tersedia tertinggi dijumpai pada perlakuan S2 (Monokultur Kedelai) yakni 15,09 %. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Suratmini 2004) yang menyatakan pemberian 15 t ha-1 pupuk kadang sapi meningkatkan kadar air dari 27,22% menjadi 29,11% serta meningkatkan ruang pori 62,32% menjadi 63,09% (Muku, 2002) juga mendapatkan pemupukan pupuk kandang sapi 15 t ha -1 pada bawang merah menurunkan berat volume dari 0,14 g cm-3 menjadi 0,12 cm-3 dan meningkatkan kadar air tanah dari 15,87% menjadi 17,52%. Pengaruh nyata akibat pola tanam diduga adanya kombinasi pemberian bahan pembenah tanah baik itu pupuk kandang, biochar dan NPK. Nilai kadar air tanah pF 4,2 tertinggi dijumpai pada perlakuan S1 (Monokultur Jagung) yakni 18,26 % dan terendah dijumpai pada S2 (Monokultur Kedelai) yakni 17,29 %. yang berbeda nyata dengan perlakuan pola tanam lainnya, kecuali pada perlakuan S3 (Tumpang Sari Jagung Kedelai) yakni 17,87 %. Sedangkan air tersedia tertinggi dijumpai pada perlakuan S2 (Monokultur Kedelai) yakni 15,09 %. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Curtis and Claassen 2005) pupuk organik dapat meningkatkan kadar air tersedia bagi tanaman. Namun Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa akibat perlakuan pola tanam pada kedalaman sub soil tidak berpengaruh nyata pada kadar air tanah pada pF 2,54 dan pF 4,2. A125 Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana (SNP) Unsyiah 2017, April 13, 2017, Banda Aceh, Indonesia Permeabilitas Tanah Cepat atau lambatnya air mengalir di dalam tanah diindikasi oleh besar kecilnya angka permeabilitas tanah. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pemberian perlakuan bahan pembenah tanah dan pola tanam pada dua kedalaman top soil dan sub soil tidak berpengaruh nyata pada permeabilitas tanah, kecuali pada sub soil akiba pola tanam. Tabel 5. Rata - Rata Nilai Permeabilitas Tanah Akibat Pemberian Bahan Pembenah Perlakuan Bahan Pembenah Tanah NPK 0.4 t Biochar 10 t ha-1 Pukan 10 t ha-1 Biochar 10 t ha-1 + NPK 0.4 t Pukan 10 t ha-1 + NPK 0.4 t BNT 0,05 Permeabilitas Tanah (cm jam-1) 0-20 cm 20-40 cm 15,50 16,43 16,54 16,40 16,28 - 16,29 16,11 16,54 16,25 16,99 - Tabel 6. Rata - Rata Nilai Permeabilitas Tanah Akibat Pemberian Bahan Pola Tanam Perlakuan Permeabilitas Tanah (cm jam-1) 0-20 cm 20-40 cm Pola Tanam S1 Monokultur Jagung S2 Monokultur Kedelai S3 Tumpang Sari Jagung Kedelai BNT 0,05 16,25 16,38 16,06 - 17,06 b 16,39 ab 15,86 a 0,75 Keterangan : Angka - Angka yang Diikuti Huruf yang Sama pada Kolom Sama Tidak Berbeda Nyata Menurut Uji BNT 0,05 Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai permeabilitas tanah pada kedalaman sub soil tertinggi dijumpai pada perlakuan Monokultur Jagung yakni 17,06 cm jam-1 yang berbeda dengan seluruh perlakuan lainnya. Kecuali pada perlakuan Monokultur Kedelai yakni 16,39 cm jam 1. Sedangkan nilai permeabilitas terendah dijumpai pada perlakuan Tumpang Sari Jagung Kedelai dengan nilai 15,86 cm jam-1. Permeabilitas merupakan kecepatan bergeraknya suatu cairan pada suatu media dalam keadaan jenuh (Haridjaya et al., 1990). Permeabilitas tanah adalah kemampuan tanah untuk meneruskan air atau udara yang digolongkan dalam kelas permeabilitas tanah. Diduga tingginya nilai permeabilitas tanah pada perlakuan pola tanam adanya kombinasi bahan pembenah tanah dengan pola tanam, sehingga pada faktor perlakuan pola tanam memberikan pengaruh sangat nyata pada perlakuan pola tanam. Permeabilitas Tanah akibat Interaksi Bahan Pembenah Tanah dan Pola Tanam Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa interaksi perlakuan bahan pembenah tanah dan pola tanam pada kedalaman top soil berpengaruh sangat nyata pada permeabilitas tanah. Nilai rata-rata permeabilitas tanah akibat interaksi bahan pembenah tanah dan pola tanam dapat dilihat pada Tabel 7. A126 Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana (SNP) Unsyiah 2017, April 13, 2017, Banda Aceh, Indonesia Tabel 7. Rata - Rata Nilai Permeabilitas Tanah dan Pola Tanam Bahan Pembenah Tanah NPK 0.4 t Biochar 10 t ha-1 Pukan 10 t ha-1 Biochar 10 t ha-1 + NPK 0.4 t Pukan 10 t ha-1 + NPK 0.4 t BNT 0,05 Akibat Interaksi Bahan Pembenah Tanah Pola Tanam Permeabilitas Tanah (cm jam-1) 0-20 cm S1 S2 S3 14,48Aa 15,74Abab 16,29Bab 15,52Aab 16,87Aabc 16,89Ab 17,95Cd 16,24Ababc 15,42Aa 17,67Cd 15,70Aa 15,83Abab 15,64Aabc 17,33Cc 15,88ABab 1,43 Keterangan : Angka - Angka yang Diikuti Huruf yang Sama pada Kolom Sama Tidak Berbeda Nyata Menurut Uji BNT 0,05 . S1 adalah Monokultur Jagung, S2 Monokultur Kedelai, dan S3 Tumpang Sari Jagung Kedelai Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai rata-rata interaksi permeabilitas tanah pada kedalaman top soil tertinggi dijumpai pada perlakuan Pupuk kandang 10 t ha-1 dengan mono culture jagung yakni 17,95 cm jam-1 yang berbeda nyata antar perlakuan lainnya. Semua hasil interaksi bahan pembenah tanah dengan pola tanam menunjukkan kriteria nilai pada permeabilitas tanah pada kelas 5 yaitu daya pelolosan air agak cepat, sehingga dapat disimpulkan yang bahwa permeabilitas tanah akibat interaksi bahan pembenah tanah dengan pola tanam dapat memberikan kriteria pelolosan air pada tingkat agak cepat. Hal ini sejalan dengan pendapat (Syahrudin 1999) permeablitas tanah yang baik pada lahan kering berkisar antara 1,5-5 cm jam-1. Menurut Jamulya dan Waro (1983) cepat lambatnya permeabilitas tanah dipengaruhi oleh kandungan bahan organik, tekstur tanah, dan struktur tanah. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa interaksi perlakuan bahan pembenah tanah dan pola tanam pada kedalaman sub soil berpengaruh sangat nyata terhadap permeabilitas tanah. Tabel 8. Rata - Rata Nilai Permeabilitas Tanah Akibat Interaksi Bahan Pembenah Tanah dan Pola Tanam pada Subsoil pada Kedalaman Tanah 20-40 cm. Pola Tanam Bahan Pembenah Tanah 20-40 cm S1 S2 S3 16,19Aba 18,07Cab 14,62Aab NPK 0.4 t 17,43Bab 15,99Aabc 14,92Ab Biochar 10 t ha-1 -1 16,67ABd 15,26Aabc 17,71Ba Pukan 10 t ha 16,02Abd 17,25Ba 15,47Aab Biochar 10 t ha-1 + NPK 0.4 t Pukan 10 t ha-1 + NPK 0.4 t 19,01Cabc 15,36Ac 16,59Abab ha-1 1,67 BNT 0,05 Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai rata-rata interaksi permeabilitas tanah pada kedalaman sub soil tertinggi dijumpai pada kombinasi perlakuan pupuk kandang 10 t ha-1 + NPK 0.4 t dan pola tanam tumpang sari jagung - kedelai yaitu 19,01 cm jam-1 yang berbeda nyata antar perlakuan lainnya kecuali pada perlakuan A0S2 (NPK 0.4 t + monokultur kedelai) yakni 18,07 cm jam-1 Sedangkan nilai permeabilitas tanah terendah dijumpai pada perlakuan A0S3 (NPK 0.4 t + tumpang sari jagung – kedelai) dengan nilai 14,62 cm jam-1. Stimulasi pembentukan aggregate tanah dapat meingkatkan produktivitas budidaya pertanaian pada tanah tanah berstruktur jelek. Meskipun sering didapatkan pengaruh nyata pemberian pembenah tanah tidak nyata. Grunwald et al. (2016) membandingkan A127 Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana (SNP) Unsyiah 2017, April 13, 2017, Banda Aceh, Indonesia pengaruh beberapa pembenah tanah dan menemukan bahwa tidak ada pengaruh nyata terhadap makro aggregate tanah akibat pemberian biochar, hal ini mungkin disebabkan peningkatan mineralizasi agen agen perekat aggregat (aggregate binding agents). Kemudian Winarso (2005) menyatakan pemberian bahan organik memungkinkan pembentukkan agregat tanah, yang selanjutnya akan memperbaiki permeabilitas dan peredaran udara tanah, akar tanaman mudah menembus lebih dalam dan luas sehingga tanaman kokoh dan lebih mampu menyerap hara tanaman. Lebih lanjut Hansen et al. (2004) menyatakan bahwa aplikasi pupuk kandang dapat menyediakan kebutuhan nitrogen tanaman jagung meskipun dalam jumlah relatif sedikit. Stabilitas Agregat Tanah Stabilitas aggregate tanah dilaporkan dengan satuan indeks stabilitas aggregate. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pemberian bahan pembenah tanah dan pola tanam (Tabel 9 dan 10) pada kedalaman top soil dan sub soil tidak berpengaruh nyata pada indeks stabilitas agregat tanah begitu juga dengan akibat pola tanam. Tabel 9. Rata - Rata Nilai Indeks Stabilitas Agregat Tanah Akibat Bahan Pembenah Tanah pada Ultisol Sifat Fisika Tanah Indeks Stabilitas Agregat Tanah Perlakuan 0-20 cm 20-40 cm Bahan Pembenah Tanah A0 NPK 0.4 t 46.22 46.84 A1 Biochar 10 t ha-1 47.88 47.64 A2 Pukan 10 t ha-1 46.99 46.43 A3 Biochar 10 t ha-1 +NPK 0.4 t 48.09 48.32 A4 Pukan 10 t ha-1 + NPK 0.4 t 46.76 47.18 BNT 0,05 Tablel 9 menunjukkan bahwa pemberian pembenah tanah meningkatkan indeks stabilitas aggregate tanah meskipun tidak nyata. Herath et al. (2013) juga mendapakan bahwa biochar amendment meningkatkan stabilitas aggregat tanah>17% dibandingkan control, dan peningkatan ini lebih kecil yaitu berkisar dari 4 – 16%. Tabel 10. Rata - Rata Nilai Indeks Stabilitas Agregat Tanah Akibat Perlakuan Pola Tanam pada Ultisol Sifat Fisika Tanah Indeks Stabilitas Agregat Tanah Perlakuan 0-20 cm 20-40 cm Pola Tanam S1 Monokultur Jagung 46.94 47,28 S2 Monokultur Kedelai 47.76 47,33 S3 Tumpang Sari Jagung Kedelai 46.86 47,23 BNT 0,05 Kesimpulan 1. Pembenah tanah dan pola tanam memberikan efek yang sama yaitu tidak memberikan pengaruh nyata terhadap berat volume tanah, porositas tanah, kadar air tanah pada pF 2.54 dan 4.2, permeabilitas tanah serta indeks stabilitas aggregate tanah. 2. Tidak terdapat interaksi antara perlakuan pembenah tanah dengan pola tanam terhadap semua sifat fisika tanah kecuali permeabilitas tanah pada dua kedalaman yaitu top dan sub soil. A128 Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana (SNP) Unsyiah 2017, April 13, 2017, Banda Aceh, Indonesia Ucapan Terimakasih Kami mengucapkan terimakasih kepada semua anggota proyek “Improving Soil and Water Management and Crop Productivity of Dray land Agriculture Systems of Aceh and New South Wales (ACIAR PROJECT NO. SMCN/2012/103). Daftar Pustaka Adimihardja, A., I. Juarsah, U. Kurnia. (2000). Pengaruh Penggunaan Berbagai Jenis dan Takaran Pupuk Kandang Terhadap Produktivitas Tanah Ultisol Terdegradasi di Desa Batin, Jambi. Hlm 303-319 dalam Prosiding Seminar Sumberdaya Lahan, Iklim, dan Pupuk. Buku II. Lido, 6-8 Desember 1999. Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat. Badan Litbang Pertanian. Bogor. Adiningsih, J.S., D. Setyorini, T. Prihatini. (1995). Pengelolaan Hara Terpadu Untuk Mencapai Produksi Pangan yang Mantap dan Akrab Lingkungan. hlm. 55-69. Dalam Prosiding Pertemuan Teknis Penelitian Tanah dan Agroklimat: Makalah Kebijakan. Bogor, 10-12 Januari 1995. Puslittanak, Bogor. Arsyad, S. (1975). Fisika Tanah : Dasar-Dasar Sifat Fisika dan Proses. IPB. Bogor. 2000. Konservasi Tanah dan Air. Serial Pustaka IPB press. IPB pres. 290 hlm. Curtis, M. J, V.P. Claassen. (2005). Compost incorporation increases plant available water in a drastically disturbed serpentine soils. Soil science. Erfandi, D., U. Kurnia, I. Juarsah. (2004). Pemanfaatan Bahan Organik Dalam Perbaikan Sifat Fisik dan Kimia Tanah Ultisol. Hlm 77-85. Prosiding Semnas. Pendayagunaan Tanah Masam, Buku II, Puslitbang Tanah dan Agroklimat, Bogor. Grundwald, D., M. Kaiser, B. Ludwig. Effect of biochar and organic fertilizer on C mineralization and macro-aggregat dynamics under incubation temperatures. Soil Till. Res. 164, 11-17. Hansen, D.J., A.M. Blackmer, P. Mallarino, M.A. Wuebker. (2004). Performance-Based Evaluation of Guidelines for Nitrogen Fertilizer Application after Animal Manure. Agronomy Journal. Vol.96, No.1:34-41. Haridjaya, O.K. Murtilaksono, Sudarmo dan L.M. Rachman. (1990). Hidrologi Pertanian Jurusan Tanah, Fakultas Pertanian IPB. Bogor. Hasnudi dan Eniza (2004). Rencana Pemanfaatan Lahan Kering Untuk Pengembangan Usaha Peternakan Ruminansia dan Usaha Tani Terpadu di Indonesia. Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Herath, H,M,S.K., M. Camps-Arbestain, M. Hedley. (2013). Effect of biochar on soil physical properties in two contrasting soils: an Alfisol and an Andisol. Geoderma, 209–210, pp. 188–197 http://dx.doi.org/10.1016/j.geoderma.2013.06.016 Jamulya dan S. Woro. (1983). Pengantar Geografi Tanah. Diktat Kuliah. Fakultas Geografi UGM. Yogyakarta. Jeffey, S., F.G.A. Verheijen, M. van der Velde, A.C. Bastos. (2011). A quatitative review of the effects of biochar application to soils on crop productivity using meta-analysis. Agriculture, Ecosystems and Environment. 144 . 175-187 Kuzyakov, Y., I. Subbotina, H. Chen, I. Bogomolova, X. Xu. (2009). Black carbon decomposition and incorporation into soil microbial biomass estimated by C-14 labeling. Soil Biol. Biochem., 41, pp. 210–219. Latuponu, H. (2010). Pemanfaatan Limbah Sagu Sebagai Bahan Aktif Biochar Untuk Meningkatkan Efisiensi Serapan Hara di Ultisol. Lembaga Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Gadjah mada. Yogyakarta. Lehmann, J. J. Gaunt, and M. Rondon. (2006). Biochar soil Manegement on Highly Weathered Soils in the Humid Tropics. P: 571-530 in Biological Approaches to sustainable Soil Systems (Norman Uphoffet al Eds.). Tylor and Francis Group PO Box 409267 Atlanta, GA 30384- 9267. Marzuki, Sufardi dan Manfarizah. (2012). Sifat Fisika dan Hasil Kedelai (Glycine Max L) pada Tanah Terkompaksi Akibat Cacing Tanah dan Bahan Organik. Jurnal Manajemen Sumberdaya Lahan, volume 1(1). A129 Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana (SNP) Unsyiah 2017, April 13, 2017, Banda Aceh, Indonesia Muku, O.M. (2002). Pengaruh Jarak Tanam Antar Barisan dan Macam Pupuk Organik Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Bawang Merah (Allium ascalonicum L.) di Lahan Kering. (tesis). Denpasar: Universitas Udayana. PT Petrokimia. (2012). http://www.petrokimia-gresik.com/. Gresik. Sohi, S.P., E. Krull, E. Lopez-Capel, R. Bol. (2010). A review of biochar and its use and function in soil. Advances in Agronomy, 105, pp. 47–82 Subagyo, H., N. Suharta, dan A.B. Siswanto. (2004). Tanah-Tanah Pertanian di Indonesia. hlm. 21 − 66. Dalam A. Adimihardja, L.I. Amien, F. Agus, D. Djaenudin (Ed.). Sumberdaya Lahan Indonesia dan Pengelolaannya. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat. Bogor. Suratmini, N.P. (2004). Pengaruh Dosis Pupuk Nitrogen dan Pupuk Kandang Sapi Terhadap Hasil, Kadar Gula Biji dan Kadar Protein Kasar Brangkasan Jagung Manis (Zea mays saccharata Sturt). (tesis). Denpasar: Universitas Udayana. Sutanto, R. (2002). Dasar – dasar Ilmu Tanah Konsep dan Kenyataan. Kanisius, Yogyakarta. (2005). Dasar-Dasar Ilmu Tanah: Konsep dan Kenyataan. Penerbit Kanisius, Yogyakarta. Sutedjo, M. M. Dan A. G. Kartasapoetra. (1991). Pupuk dan Cara Pemupukan. Bina Aksara. Jakarta. Syahruddin. (1999). Pemberian Pupuk Kandang Memperbaiki Sifat Fisik dan Kimia Tanah. Lokakarya Fungsional Nonpeneliti. Bogor. Suwardjo, H., A. Abdurachman, and S. Abunyamin. (1989). The use of crop residue mulch to minimize tillage frequency. Pembrt.Pen. Tanah dan Pupuk 8:31-37. Tisdale, S. I. and W.G. Nelson. (1975). Soil Fertility and Fertilizer. Mc Millan Publisher Co., New York. 75 p. Winarso, S. (2005). Kesuburan Tanah: Dasar Kesehatan dan Kualitas Tanah. Gaya Media. Yogyakarta. Wiskandar, (2002). Pemanfaatan Pupuk Kandang Untuk Memperbaiki Sifat Fisik Tanah di Lahan Kritis yang Telah Diteras. Konggres Nasional VII. A130