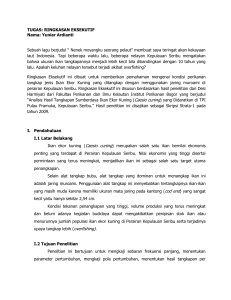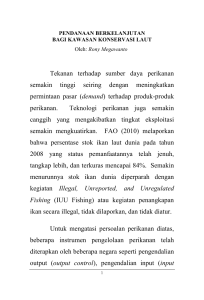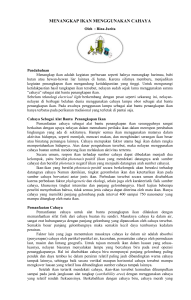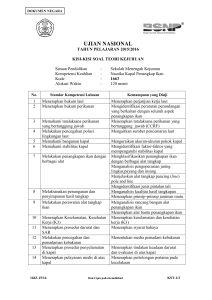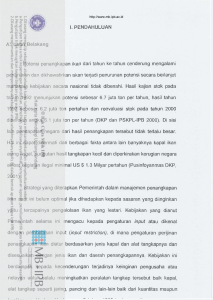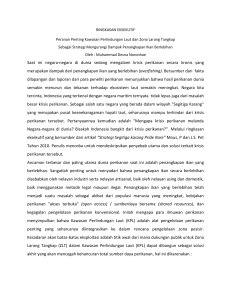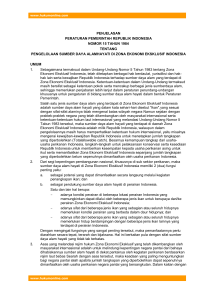ANALISIS HASIL TANGKAPAN SUMBERDAYA IKAN EKOR
advertisement

i ANALISIS HASIL TANGKAPAN SUMBERDAYA IKAN EKOR KUNING (Caesio cuning) YANG DIDARATKAN DI PPI PULAU PRAMUKA, KEPULAUAN SERIBU DESI HARMIYATI SKRIPSI DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2009 i ii PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: Analisis Hasil Tangkapan Sumberdaya Ikan Ekor Kuning (Caesio cuning) yang Didaratkan di PPI Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu adalah benar merupakan hasil karya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Semua sumber dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini. Bogor, 4 Desember 2009 Desi Harmiyati C24052659 ii iii RINGKASAN Desi Harmiyati. C24052659. Analisis Hasil Tangkapan Sumberdaya Ikan Ekor Kuning (Caesio cuning) yang Didaratkan di PPI Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Dibimbing oleh Mennofatria Boer dan Zairion. Ikan ekor kuning merupakan salah satu sumberdaya ikan ekonomis penting yang terdapat di Perairan Kepulauan Seribu. Nilai ekonomis yang tinggi disertai permintaan yang terus meningkat, menjadikan ikan ini sebagai salah satu target utama penangkapan. Namun pada kenyataannya sumberdaya ikan ekor kuning mengalami tekanan penangkapan yang akan berdampak negatif terhadap populasi ikan tersebut. Penelitian ini dilakukan di Perairan Kepulauan Seribu selama periode bulan Maret sampai Mei 2009, dengan tujuan untuk mengkaji sebaran frekuensi panjang, menentu‐ kan parameter pertumbuhan, mengkaji pola pertumbuhan, menentukan nilai hasil tangkapan per satuan upaya, dan menduga musim penangkapan yang baik, guna memberikan suatu usulan model pengelolaan yang sesuai bagi sumberdaya ikan tersebut. Jenis data yang dikumpulkan untuk keperluan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari pengambilan ikan contoh dan wawancara terhadap nelayan berdasarkan kuisioner, sedangkan data sekunder terdiri dari data hasil tangkapan dan upaya tangkap beberapa tahun terakhir, dokumen atau literatur yang mendukung penelitian. Dari 13 jumlah nelayan muroami, ikan contoh yang di‐ ambil berasal hanya dari satu nelayan saja yang mendarat di PPI Pulau Pramuka dengan dasar pertimbangan mengambil 10% dari total jumlah nelayan muroami yang ada. Nelayan yang terpilih diambil secara acak dengan menggunakan metode penarik‐ an contoh acak sederhana (simple random sampling). Pengambilan contoh ikan di‐ lakukan dengan metode penarikan contoh berlapis (stratified random sampling) adalah penarikan contoh yang dilakukan dengan cara populasi dibagi menjadi beberapa lapis‐ an berdasarkan karakteristiknya. Ikan contoh dibedakan berdasarkan ukurannya yaitu kecil, sedang, dan besar. Total ikan contoh yang diambil sebanyak 150 ekor setiap bulan. Pengambilan contoh responden dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling atau pemilihan responden dengan sengaja berdasarkan kesediaan anggota populasi. Ikan ekor kuning yang diamati berjumlah 450 ekor dengan kisaran panjang antara 75‐294 mm yang terbagi dalam 22 kelas dengan interval kelas sebesar 10 mm. Kelompok ukuran ikan dipisahkan dengan metode Bhattacarya menggunakan bantuan software FISAT II. Selanjutnya koefisien pertumbuhan (K) dan panjang asimtotik (L∞) diduga dengan plot Ford Walford, dan umur teoritis pada saat panjang sama dengan nol (t0) menggunakan rumus Pauly. Berdasarkan metode Bhattacharya, didapat kurva normal yang menggambarkan jumlah kohort sebaran frekuensi panjang yang ada. Persamaan pertumbuhan ikan ekor kuning jantan adalah Lt = 303,00 (1‐e‐0,55(t+0,0793)), sedangkan persamaan pertumbuhan ikan ekor kuning betina adalah Lt = 303,98 (1‐e‐ 0,19(t+0,2389)) dan persamaan pertumbuhan ikan ekor kuning secara total adalah Lt = 303,28 (1‐e‐0,35(t+0,1268)). Nilai b didapat dari hubungan panjang berat ikan ekor kuning di Perairan Kepulauan Seribu sebesar 3,009. Pola pertumbuhan ikan ekor kuning isometrik (p<0,05) dengan persamaan pertumbuhan W=2x10‐5L3,009, sedangkan nilai b ikan ekor kuning betina sebesar 3,242 dengan persamaan pertumbuhan W=6x10‐ 6L3,242, pola pertumbuhan ikan ekor kuning betina allometrik positif (p<0,05) dan nilai b dari ikan ekor kuning jantan sebesar 2,579 dengan persamaan pertumbuhan iii iv W=17x10‐5L2,579, pola pertumbuhan ikan ekor kuning jantan allometrik negatif (p<0,05). Perkembangan hasil tangkapan ikan ekor kuning yang tertangkap dengan meng‐ gunakan alat tangkap muroami di Perairan Kepulauan Seribu pada tahun 2003‐2007 terjadi kenaikan. Hal ini diduga karena pengaruh musim setiap tahun berubah, selain itu karena bertambahnya jumlah kapal penangkapan dan alat tangkap mengakibatkan menurunnya nilai hasil produksi tangkapan per tahun. Total tangkapan ikan ekor kuning di Kepulauan Seribu periode bulan Mei 2007‐Maret 2008 pada kedua musim tertinggi pada bulan Maret dan bulan November. Berdasarkan hasil penelitian ini, alternatif strategi pengelolaan sumberdaya ikan ekor kuning diantaranya adalah pencegahan overfishing dapat dilakukan dengan: (1) pengaturan alat tangkap, yakni pengaturan mesh size jaring muroami pada bagian kantong agar lebih besar dari 1 inchi; (2) pengaturan upaya penangkapan; (3) dalam jangka pendek dapat dilakukan schedule of fishing, yaitu kegiatan pengaturan pe‐ nangkapan seperti adanya sistem buka tutup untuk suatu lokasi penangkapan; (4) perlunya menerapkan sistem monitoring serta pendataan secara sistematis dan kontinu terhadap produksi ikan yang bernilai jual, ikan konsumsi, bahkan ikan yang terbuang (by catch). iv v ANALISIS HASIL TANGKAPAN SUMBERDAYA IKAN EKOR KUNING (Caesio cuning) YANG DIDARATKAN DI PPI PULAU PRAMUKA, KEPULAUAN SERIBU DESI HARMIYATI C24052659 Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perikanan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2009 v vi PENGESAHAN SKRIPSI Judul Skripsi Nama NIM Program Studi : Analisis Hasil Tangkapan Sumberdaya Ikan Ekor Kuning (Caesio cuning) yang Didaratkan di PPI Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu : Desi Harmiyati : C24042659 : Manajemen Sumberdaya Perairan Disetujui Komisi Pembimbing Pembimbing I Pembimbing II Prof. Dr. Ir. Mennofatria Boer, DEA NIP: 19570928 198103 1 006 Ir. Zairion, M.Sc. NIP: 19640703 199103 1 003 Diketahui Ketua Departeman Manajemen Sumberdaya Perairan Dr. Ir. Yusli Wardiatno, M.Sc. NIP: 19660728 199103 1 002 Tanggal Lulus : 4 November 2009 vi vii PRAKATA Syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia‐ Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini berjudul “Analisis Hasil Tangkapan Sumberdaya Ikan Ekor Kuning (Caesio cuning) yang Didaratkan di PPI Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu”, disusun berdasarkan hasil penelitian di Kepulauan Seribu yang dilaksanakan pada bulan Maret sampai bulan Mei 2008 dan merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana perikanan pada Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam memberikan bimbingan, masukan, dan araharan sehingga penulis dapat penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, dikarenakan keterbatasan pengetahuan penulis. Penulis mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk berbagai pihak. Bogor, 4 Desember 2009 Penulis vii viii UCAPAN TERIMA KASIH Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Prof. Dr. Ir. Mennofatria Boer, DEA selaku dosen pembimbing I dan Ir. Zairion M.Sc., selaku dosen pembimbing II atas bimbingan, arahan, dan masukan yang diberikan selama penyusunan skripsi. 2. Ir. Nurlisa A. Butet, M.Sc., selaku dosen penguji tamu dan Dr. Ir. Yunizar Ernawati, M.S. selaku dosen penguji dari komisi pendidikan S1 atas saran, nasehat, dan perbaikan yang diberikan. 3. Ir. Sigid Haryadi, M.Sc. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan selama penulis menempuh pendidikan di Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan. 4. Keluarga tercinta; Papa, mama, dan semua keluarga besar serta Kakanda Abidzar Al Giffari yang baru bertemu setelah dewasa atas doa, kasih sayang, dukungan, dan motivasinya. 5. Balai Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu dan Suku Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. 6. Nelayan Kepulauan Seribu dan masyarakat Kepulauan Seribu yang telah memberikan do’a dan membantu memberikan tumpangan rumahnya selama penulis melakukan penelitian. 7. Para staf Tata Usaha MSP terutama Mba Widaryanti, Bagian Manajemen Sumberdaya Perikanan (MSPi) serta seluruh civitas Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. 8. Andika Septiawan (PSP 42) selaku partner penelitian, Vivin Kusuma Wardani, Bonang (ITK 41), rekan‐rekan seperjuangan MSP 41 (Mba Ami, Mba Ichel, Bang Ray), rekan‐rekan seperjuangan MSP 42, rekan‐rekan seperjuangan di Pulau Seribu (Avie, Ebit, Nano, Olva,), serta rekan‐rekan Wisma Bata Merah (Ary, Reiza, Adit, Nunu, Iboth, Zulmi, Freddy, Dion) atas doa, bantuan, dukungan, kesabaran, kerjasama, dan semangatnya kepada penulis selama masa perkuliahan hingga pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi serta seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu. viii ix RIWAYAT HIDUP Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 1987 yang merupakan anak ke‐5 dari lima orang bersaudara dari pasangan Bapak Abang Munir (almarhum) dan Ibu Subiyanti. Pendidikan formal penulis dimulai di SDN Malaka Jaya 05 Jakarta (1993‐1999). Setelah menyelesaikan pendidikan dasar penulis melanjutkan pendidikan di SLTP N 139 Jakarta (1999‐2002), dan menempuh pendidikan menengah atas di SMU N 91 Jakarta (2002‐2005). Pada tahun 2005 penulis diterima di Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur USMI (Undangan Seleksi Masuk IPB). Setelah melewati tahap Tingkat Persiapan Bersama selama 1 tahun, penulis diterima di Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Selama mengikuti perkuliahan penulis aktif mengikuti kegiatan Himpunan Mahasiswa Manajemen Sumberdaya Perairan (HIMASPER). Penulis diberi kesempatan dan kepercayaan menjadi Asisten Mata Kuliah Metode Penarikan Contoh (2007/2008) dan Asisten Mata Kuliah Dasar‐dasar Pengkajian Stok Ikan (2008/2009). Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana, penulis menyusun skripsi dengan judul “Analisis Hasil Tangkapan Sumberdaya Ikan Ekor Kuning (Caesio cuning) yang Didaratkan di PPI Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu”. ix x DAFTAR ISI Halaman DAFTAR TABEL ............................................................................................................................ xii DAFTAR GAMBAR .......................................................................................................................... xiii DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................................................... xiv 1. PENDAHULUAN ........................................................................................................................ 1.1. Latar Belakang ................................................................................................................ 1.2. Rumusan Masalah ......................................................................................................... 1.3. Tujuan Penelitian .......................................................................................................... 1.4. Manfaat Penelitian ........................................................................................................ 2. TINJAUAN PUSTAKA .............................................................................................................. 2.1. Sumberdaya Ikan Ekor Kuning ................................................................................ 2.1.1. Klasifikasi dan deskripsi .......................................................................... 2.1.2. Habitat dan kebiasaan hidup ................................................................. 2.2. Alat Tangkap Ikan Ekor Kuning .............................................................................. 2.3. Analisis Frekuensi Panjang ....................................................................................... 2.4. Pertumbuhan .................................................................................................................. 2.5. Hubungan Panjang Berat ........................................................................................... 2.6. Kondisi Wilayah Kepulauan Seribu ....................................................................... 2.7. Perikanan Tangkap di Kepulauan Seribu ............................................................ 2.8. Musim Penangkapan Ikan di Kepulauan Seribu ............................................... 2.9. Tangkapan Per Satuan Upaya (TPSU)................................................................... 2.10. Strategi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan ................................................... 3. METODE PENELITIAN ........................................................................................................... 3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian .................................................................................... 3.2. Alat dan Bahan ............................................................................................................... 3.3. Pengumpulan Data ....................................................................................................... 3.4. Analisis Data .................................................................................................................... 3.4.1. Sebaran frekuensi panjang ..................................................................... 3.4.2. Parameter pertumbuhan (L∞, K) dan t0 ............................................ 3.4.3. Hubungan panjang berat ......................................................................... 3.4.4. Tangkapan per satuan upaya ................................................................ 4. HASIL DAN PEMBAHASAN ................................................................................................... 4.1. Hasil............... ..................................................................................................................... 4.1.1. Wilayah administrasi Kepulauan Seribu .......................................... 4.1.2. Fasilitas yang tersedia di PPI Pulau Pramuka ............................... 4.1.3. Sebaran frekuensi panjang ikan ekor kuning ................................. 4.1.4. Parameter pertumbuhan (L∞, K) dan t0 ............................................ 4.1.5. Pertumbuhan ................................................................................................ 4.1.6. Hubungan panjang berat ......................................................................... 4.1.7. Tangkapan per satuan upaya ................................................................. x 1 1 2 2 2 3 3 3 4 5 5 7 8 9 10 11 11 11 14 14 14 14 16 16 17 18 19 20 20 20 21 22 24 27 27 31 xi 4.2. Pembahasan .................................................................................................................... 4.2.1. Sebaran frekuensi panjang ikan ekor kuning ................................. 4.2.2. Parameter pertumbuhan (L∞, K) dan t0 ............................................ 4.2.3. Pertumbuhan ................................................................................................ 4.2.4. Hubungan panjang berat ......................................................................... 4.2.5. Tangkapan per satuan upaya ................................................................. 4.2.6. Alternatif strategi pengelolaan sumberdaya ikan ekor kuning 5. KESIMPULAN DAN SARAN ................................................................................................... 5.1. Kesimpulan............... ....................................................................................................... 5.2. Saran............................ ....................................................................................................... 33 33 34 35 36 37 39 41 41 41 DAFTAR PUSTAKA.................. ...................................................................................................... 43 LAMPIRAN ........................................................................................................................................ 47 xi xii DAFTAR TABEL Halaman 1. Letak geografis Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ................................. 21 2. Hasil analisis masing‐masing kelompok ukuran ikan ekor kuning jantan ...... 26 3. Hasil analisis masing‐masing kelompok ukuran ikan ekor kuning betina ...... 26 4. Hasil analisis masing‐masing kelompok ukuran ikan ekor kuning secara total ............................ .................................................................................................................. 26 5. Parameter pertumbuhan (L∞, K) dan t0.......................................................................... 27 6. Hasil perhitungan panjang dan berat ikan ekor kuning .......................................... 29 7. Hasil tangkapan dan upaya tangkap ikan ekor kuning di Kepulauan Seribu.. 31 xii xiii DAFTAR GAMBAR Halaman 1. Ikan ekor kuning (Caesio cuning) ..................................................................................... 3 2. Sebaran frekuensi panjang ikan ekor kuning setiap kelas (a) bulan Maret, (b) bulan April, (c) bulan Mei, (d) secara total ............................................................ 23 3. Kelompok ukuran ikan ekor kuning (a) jantan, (b) betina, (c) secara total .... 25 4. Kurva pertumbuhan ikan ekor kuning (a) jantan, (b) betina, (c) secara total 28 5. Hubungan panjang berat ikan ekor kuning (a) jantan, (b) betina, (c) secara total ..................................................................................................................... 30 6. Tangkapan per satuan upaya ikan ekor kuning di Kepulauan Seribu ............... 32 7. Total tangkapan ikan ekor kuning setiap bulan di Kepulauan Seribu periode Mei 2007‐Maret 2009 ........................................................................................... 32 xiii xiv DAFTAR LAMPIRAN Halaman 1. Jaring muroami ..................................................................................................................... 48 2. Alat penggiring ikan di Kepulauan Seribu .................................................................... 50 3. Jenis ikan yang tertangkap di Perairan Kepulauan Seribu .................................... 51 4. Peta lokasi daerah penangkapan ikan ekor kuning di Kepulauan Seribu ....... 52 5. Alat yang digunakan dalam penelitan ............................................................................ 53 6. Formulir kuisioner ................................................................................................................. 54 7. Skema pelabuhan perikanan .............................................................................................. 57 8. Fasilitas yang tersedia di Pelabuhan Perikanan Pulau Pramuka ........................ 59 9. Data panjang dan berat ikan contoh tiap bulan selama penelitian .................... 60 10. Perhitungan pendugaan parameter pertumbuhan (L∞, K) dan t0 ...................... 64 11. Uji t nilai b pada hubungan panjang berat ikan ekor kuning ................................ 65 12. Tahap operasional alat tangkap muroami .................................................................... 68 13. Bagian‐bagian alat tangkap muroami ............................................................................ 69 14. Spesifikasi kapal muroami .................................................................................................. 70 15. Kapal muroami ..................................................................................................................... 71 xiv 1 1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Wilayah Perairan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu banyak dijumpai berbagai jenis ikan karang, baik ikan hias yang hidup di sekitar daerah terumbu karang maupun jenis‐jenis ikan konsumsi yang hidup disekitar perairan agak dalam. Ikan‐ ikan di daerah ini, memiliki keanekaragaman baik jenis, warna, maupun ukuran. Berdasarkan hasil pengamatan Balai Konservasi Taman Laut Nasional Kepulauan Seribu DepHut (2004), terdapat jenis‐jenis ikan karang di Perairan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu sebanyak 31 famili dengan 232 spesies. Salah satu jenis ikan karang yang dominan di Perairan Kepulauan Seribu adalah ikan ekor kuning. Produksi ikan ekor kuning pada tahun 2006 sebanyak 1.064 ton (sebesar 82,4% dari total produksi), dengan total nilai produksi sebanyak Rp. 6.016.800.000 dan produksi ikan ekor kuning pada tahun 2005 sebanyak 955,9 ton (sebesar 78,6% dari total produksi), dengan total nilai produksi Rp. 5.421.983.000. Dari data tersebut produksi ikan mengalami peningkatan sebesar 3,8% dari tahun 2005 ke tahun 2006. Jenis alat tangkap yang dominan digunakan untuk menangkap ikan ekor kuning antara lain adalah bubu (portable traps) dan jaring muroami (Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Provinsi DKI Jakarta 2007a). Ikan ekor kuning merupakan jenis ikan konsumsi yang memiliki nilai ekonomis penting. Dengan semakin meningkatnya permintaan komoditas dan semakin bertambahnya angkatan kerja disektor penangkapan mengakibatkan semakin meningkatnya tekanan penangkapan terhadap sumberdaya ikan karang. Penambahan jumlah upaya penangkapan pada batas waktu tertentu akan menyebabkan peningkatan produksi, tetapi apabila terus terjadi penambahan upaya, maka pada suatu saat akan terjadi penurunan stok. Apabila kondisi pola pemanfaatan sumberdaya ikan ekor kuning yang ada pada saat ini tetap berjalan, diduga dalam jangka panjang dapat mengakibatkan penurunan stok sumberdaya bahkan dapat terancam punah. Kajian potensi sumberdaya ikan per jenis pada berbagai lokasi sangat diperlukan untuk memahami kondisi sebenarnya sumberdaya ikan di Perairan Kepulauan Seribu. 1 2 1.2. Rumusan Masalah Ikan ekor kuning adalah komoditas bernilai ekonomi tinggi di Kepulauan Seribu. Selain alat tangkap bubu, alat tangkap yang dominan untuk menangkap ikan ini adalah jaring muroami. Penggunaan alat tangkap ini menyebabkan tertangkapnya ikan‐ikan yang masih muda karena memiliki ukuran mata jaring pada kantong (cod end) yang sangat kecil yaitu hanya sekitar 2,54 cm. Kondisi tekanan penangkapan yang tinggi, volume produksi yang terus meningkat dan belum adanya kegiatan budidaya dapat mengakibatkan penipisan stok ikan atau menurunnya jumlah populasi ikan ekor kuning di Perairan Kepulauan Seribu serta terjadinya upaya tangkap lebih (overfishing). Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya pengelolaan agar pemanfaatan ikan ekor kuning yang berkelanjutan dapat tercapai. Dalam hal ini diperlukan informasi dasar mengenai biologi sumberdaya ikan ekor kuning seperti pertumbuhan agar status populasi ikan ekor kuning saat ini dapat diketahui. 1.3. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sebaran frekuensi panjang, menentukan parameter pertumbuhan, mengkaji pola pertumbuhan, menentukan hasil tangkapan per satuan upaya, dan menduga musim penangkapan yang baik, guna memberikan suatu usulan model pengelolaan yang sesuai bagi sumberdaya ikan tersebut. 1.4. Manfaat Penelitian Sebagai langkah awal pengelolaan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu masukan dari aspek biologi dalam merumuskan upaya pengelolaan ikan ekor kuning. 2 3 2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Sumberdaya Ikan Ekor Kuning 2.1.1. Klasifikasi dan deskripsi Ikan ekor kuning merupakan salah satu sumberdaya ikan konsumsi di perairan karang dan merupakan target penangkapan muroami. Menurut Nelson (2006), klasifikasi ikan ekor kuning adalah sebagai berikut : Dunia : Animalia Filum : Chordata Kelas : Actinopterygii Ordo : Perciformes Famili : Caesionidae Genus : Caesio Spesies : Caesio cuning 2 cm Gambar 1. Ikan ekor kuning (Caesio cuning) (dokumentasi pribadi 2009) Menurut Kottelat et al. 1993 dan Murniyati 2004, ikan ekor kuning disebut juga redbelly yellowtail fusilier. Ciri‐ciri ikan ekor kuning yaitu bentuk badan memanjang, melebar, pipih, mulut kecil, memiliki gigi‐gigi kecil, dan lancip. Dua gigi taring terdapat pada rahang bawah. Jari‐jari keras sirip punggung sebanyak 10 buah dan jari‐jari yang lemah sebanyak 15 buah. Tiga jari‐jari keras pada sirip dubur dan jari –jari yang lemah sebanyak 11 buah. Ikan ini memiliki sisik tipis sebanyak 52‐58 buah pada garis 3 4 rusuknya. Sisik‐sisik kasar di bagian atas dan di bawah garis rusuk tersusun secara horizontal, sisik pada kepala terletak dari mata. Tubuh ikan ekor kuning bagian atas sampai punggung berwarna ungu kebiruan. Bagian belakang punggung, batang ekor, sebagian dari sirip punggung berjari‐jari lemah, dan sirip dubur berwarna biru keputihan. Ekor berwarna kuning, bagian bawah kepala, badan, sirip perut, dan dada berwarna merah jambu. Pinggiran sirip punggung sedikit hitam dan ketiak sirip dada berwarna hitam (Kottelat et al. 1993). 2.1.2. Habitat dan kebiasaan hidup Ikan ekor kuning termasuk plankton feeder, yaitu pemakan plankton. Hidup di perairan pantai, karang‐karang, perairan karang, dan membentuk gerombolan besar. Panjang tubuhnya dapat mencapai panjang 35 cm tetapi pada umumnya hanya dapat mencapai 25 cm (Kuiter & Tonozuka 2004). Famili Caesionidae memiliki ciri khas yaitu hidup bergerombol (schooling) dalam ukuran yang besar dan ditemui di dekat tubir (Randal et al. 1990), berenang dengan cepat (fast swimming), dan memakan zooplankton. Ikan ekor kuning merupakan jenis ikan yang tidak melakukan migrasi ke tempat lain karena banyak terdapat pada kawasan perairan yang memiliki substrat pasir dan karang, terutama kawasan terumbu karang. Banyak terdapat di kolom perairan sepanjang tepi lereng terumbu karang. Ikan ekor kuning dapat hidup di perairan pada kedalaman 0‐40 m (Allen 2000). Daerah penyebarannya meliputi perairan laut tropis di perairan karang seluruh Indonesia, Teluk Benggala, Teluk Siam, sepanjang Pantai Laut Cina Selatan, bagian Selatan Ryukyu (Jepang), dan Perairan Tropis Australia (Subani & Barus 1989). Menurut Allen & Steene (1990), berdasarkan periode aktif mencari makan ikan terbagi menjadi dua kategori, yaitu ikan diurnal dan ikan nokturnal. Ikan‐ikan diurnal yaitu kelompok ikan yang aktif berinteraksi dan mencari makan pada siang hari. Pada malam hari ikan‐ikan diurnal akan masuk dan berlindung di dalam terumbu dan digantikan oleh ikan‐ikan nokturnal (ikan malam). Ikan diurnal karena aktif pada siang hari dan istirahat di karang pada malam hari. Ikan nokturnal meliputi Holocentridae, Apogonidae, Haemulidae, Muraenidae, Scorpaenidae, Serranidae, dan Labridae. Selain ikan diurnal dan nokturnal, ada pula ikan‐ikan yang sering melintasi ekosisten terumbu karang seperti Scombridae, Sphyraenidae (barracuda), Caesionidae (ekor kuning), dan Allopidae (hiu). 4 5 2.2. Alat Tangkap Ikan Ekor Kuning Alat tangkap yang biasanya digunakan untuk menangkap ikan karang di Kepulauan Seribu adalah jaring muroami (Lampiran 1). Menurut Subani dan Barus (1989), muroami berasal dari kata ”muro” yang merupakan jenis ikan Carangidae dan ”ami” yang berarti alat. Jika dilihat dari pengoperasiannya, muroami dapat digolongkan ke dalam drive­in­net atau alat tangkap dengan penggiring. Berdasarkan klasifikasi alat tangkap menurut Brandt (1984), muroami termasuk dalam drive­in net, dimana ikan ditangkap dengan cara menggiring ikan ke dalam alat tangkap jenis apa saja. Alat tangkap terdiri dari suatu konstruksi alat yang tetap (stasioner), ikan digiring kedalamnya oleh nelayan yang berenang atau menyelam maupun dengan menggunakan tali penggiring. Menurut Subani dan Barus (1989), satu unit alat tangkap muroami terdiri atas beberapa bagian, yaitu: (1) Bagian jaring, terdiri atas kaki panjang, kaki pendek, dan kantong (Lampiran 1). (2) Pelampung, terdiri atas pelampung yang terdapat pada tali ris atas dan tali ris bawah (Lampiran 1). Di bagian tertentu pada tali ris atas, diikatkan pelampung‐ pelampung kecil yang merupakan pelampung tetap. Pelampung tetap juga dipasang pada bagian atas mulut kantong. Selain itu, di atas mulut kantong dipasang pelampung dari bola gelas dan bambu. Kedua pelampung ini hanya dipasang pada waktu operasi penangkapan berlangsung. (3) Pemberat, pemberat dari batu diletakkan pada bagian tali ris bawah dan pada bagian bawah mulut kantong (Lampiran 1). Selain itu, pada saat operasional alat di bagian depan kaki dilengkapi dengan jangkar. (4) Penggiring atau scare line terbuat dari tali sepanjang ±25 m. Pada salah satu ujung diikatkan pelampung bambu, sedangkan pada ujung yang lainnya diikatkan alat yang menghasilkan bunyi‐bunyian dari gelang‐gelang besi. Pada sepanjang tali pengiring dilengkapi dengan daun‐daun nyiur atau terkadang kain putih. Jumlah alat pengusir disesuaikan dengan jumlah orang yang bertugas sebagai penggiring (Lampiran 2). 2.3. Analisis Frekuensi Panjang Pengkajian stok ikan (fish stock assessment) pada intinya memerlukan data komposisi umur. Pada perairan beriklim sedang, data komposisi umur biasanya dapat diperoleh melalui perhitungan terhadap lingkaran‐lingkaran tahunan pada bagian‐ 5 6 bagian keras seperti sisik dan otolith. Lingkaran‐lingkaran ini dibentuk karena adanya fluktuasi yang kuat dalam berbagai kondisi lingkungan dari musim panas ke musim dingin dan sebaliknya. Pada daerah tropis tidak terjadi perubahan musim yang sangat mencolok, oleh karena itu penggunaan lingkaran‐lingkaran musiman untuk menentukan umur sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin dilakukan. Sejumlah metode penentuan umur telah dikembangkan dengan menggunakan sejumlah struktur yang lebih lembut dengan menggunakan lingkaran‐lingkaran harian untuk menghitung umur ikan dan jumlah hari. Namun, metode ini memerlukan peralatan khusus yang relatif mahal dan tidak mungkin dapat diaplikasikan diberbagai tempat. Beberapa metode numerik telah dikembangkan yang memungkinkan dilakukannya konversi atas data frekuensi panjang ke dalam komposisi umur. Oleh karena itu, kompromi yang paling baik bagi pengkajian stok spesies tropis adalah analisis sejumlah data frekuensi panjang. Data frekuensi panjang yang dijadikan contoh dan dianalisa dengan benar dapat memperkirakan parameter pertumbuhan yang digunakan dalam pendugaan stok spesies tunggal (Pauly 1983). Analisa frekuensi panjang digunakan untuk menentukan kelompok ukuran ikan yang didasarkan kepada anggapan bahwa frekuensi panjang individu dalam suatu spesies dengan kelompok umur yang sama akan bervariasi mengikuti sebaran normal (Effendie 1997). Sejumlah data komposisi panjang dapat digunakan untuk melihat komposisi tangkapan. Panjang ikan dapat ditentukan dengan mudah dan cepat dalam investigasi di lapangan, karena panjang ikan dari umur yang sama cenderung membentuk suatu distribusi normal sehingga umur bisa ditentukan dari distribusi frekuensi panjang melalui analisis kelompok umur. Kelompok umur bisa diketahui dengan mengelompokkan ikan dalam kelas‐kelas panjang dan menggunakan modus panjang kelas tersebut untuk mewakili panjang kelompok umur. Hasil identifikasi kelompok umur dapat digunakan untuk menghitung pertumbuhan dan laju pertumbuhan (Busacker et al. in Schreck and Moyle 1990). Ketika suatu contoh besar yang tidak bias diambil dari suatu stok ikan atau invertebrata, panjang masing‐masing individu bisa diukur dan digambarkan sebagai diagram frekuensi panjang. Jika pemijahan terjadi sebagai suatu peristiwa diskret, hal ini akan menghasilkan kelompok ukuran atau kelas yang berbeda yang dibuktikan dengan puncak atau modus pada distribusi frekuensi panjang (King 1995). 6 7 2.4. Pertumbuhan Jabbar (2008) menyatakan bahwa hasil penelitiannya pada bulan Maret 2007, mendapatkan ukuran panjang ikan ekor kuning yang terkecil adalah 15,0‐15,9 cm dan ukuran yang terbesar 28,0‐28,9 cm dengan rata panjang 19,64 cm. Pada bulan Juli 2007, didapatkan data hasil pengukuran berat berkisar antara 7,1‐470 gram dengan rata‐rata 95,94 gram. Pola hubungan panjang dan berat yang menunjukkan pola pertumbuhan bersifat isometrik (b=3,021) dengan nilai koefisien determinasi (R²=0,987) yang berarti penambahan panjang ikan sama dengan pertambahan berat tubuh ikan. Pertumbuhan pada tingkat individu dapat dirumuskan sebagai pertambahan ukuran panjang atau berat dalam suatu periode waktu tertentu, sedangkan pertumbuhan populasi diartikan sebagai pertambahan jumlah. Faktor‐faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dapat digolongkan menjadi dua bagian yang besar yaitu faktor dalam dan faktor luar. Faktor‐faktor ini ada yang dapat dikontrol dan ada juga yang tidak. Faktor dalam umumnya adalah faktor yang sulit untuk dikontrol, diantaranya adalah keturunan, jenis kelamin, umur, parasit, dan penyakit (Effendie 1997). Faktor luar yang utama mempengaruhi pertumbuhan seperti suhu air, kandungan oksigen terlarut, amonia, salinitas, dan fotoperiod (panjang hari). Faktor‐ faktor tersebut berinteraksi satu sama lain dan bersama‐sama dengan faktor‐faktor lainnya seperti kompetisi, jumlah dan kualitas makanan, umur, serta tingkat kematian yang dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ikan (Effendie 1997). Faktor‐faktor yang paling banyak mempengaruhi pertumbuhan adalah jumlah dan ukuran pakan yang tersedia, jumlah individu yang menggunakan pakan yang tersedia, kualitas air terutama suhu, oksigen terlarut, umur, ukuran ikan serta kematangan gonad (Effendie 1997). Berdasarkan www.fishbase.com ukuran pertama kali matang gonad dari ikan ekor kuning berkisar antara 22‐23 cm. Umur untuk mencapai panjang maksimal ikan ekor kuning antara 18‐20 tahun (Sale 2006). Hal ini juga didukung berdasarkan penelitian Marnane et al. 2005 di Kepulauan Karimunjawa ikan ekor kuning pada umumnya mencapai tahap dewasa pada ukuran 25‐45 cm dan pada selang ukuran 33‐ 46 cm atau 2 ekor dalam 1 kg baru merupakan ukuran tangkap yang optimal dalam arti memiliki nilai ekonomis dan ekologis yang tertinggi. Berdasarkan data tersebut, maka ukuran ikan yang boleh ditangkap adalah yang memiliki panjang lebih dari ukuran matang gonadnya, hal ini disebabkan karena pada ukuran ini ikan sudah 7 8 pernah memijah dan diberikan kesempatan untuk berkembang biak sehingga tidak akan mengganggu keseimbangan populasi. 2.5. Hubungan Panjang Berat Pengukuran panjang tubuh memberikan bukti langsung terhadap pertumbuhan. Peningkatan ukuran panjang umumnya tetap berlangsung walaupun ikan mungkin dalam keadaan kekurangan makanan. Panjang dapat dengan mudah dan murah diukur di lapangan maupun laboratorium pada ikan yang masih hidup ataupun ikan yang sudah diawetkan (Anderson and Gutreuter 1983 in Dina 2008). Panjang tubuh dapat diukur dalam banyak cara dan yang umum digunakan untuk ikan adalah panjang total, panjang cagak, dan panjang baku. Panjang total adalah panjang ikan yang diukur mulai dari ujung terdepan bagian kepala sampai ujung terakhir bagian ekornya. Panjang cagak adalah panjang ikan yang diukur dari ujung terdepan sampai ujung bagian luar lekukan sirip ekor, sedangkan panjang standar atau panjang baku adalah panjang ikan yang diukur dari ujung terdepan dari kepala sampai ujung terakhir dari tulang punggungnya atau pangkal sirip ekor (Effendie 1997). Analisis hubungan panjang berat bertujuan untuk mengetahui pola pertumbuhan ikan dengan menggunakan parameter panjang dan berat. Berat dapat dianggap sebagai salah satu fungsi dari panjang. Nilai yang didapat dari perhitungan panjang berat ini adalah untuk menduga berat dari panjang atau sebaliknya. Selain itu juga dapat diketahui pola perumbuhan, kemontokan, dan pengaruh perubahan lingkungan terhadap pertumbuhan ikan (Effendie 1997). Panjang ikan sering lebih mudah didapatkan dibandingkan dengan umur atau beratnya. Effendie (1997) menyatakan bahwa jika panjang dan berat diplotkan dalam suatu gambar maka akan didapatkan persamaan W = aLb; W=berat, L=panjang, a dan b adalah suatu konstanta. Nilai b berfluktuasi antara 2,5 dan 4 tetapi kebanyakan mendekati 3 karena pertumbuhan mewakili peningkatan dalam tiga dimensi sedangkan pengukuran panjang diambil dari satu dimensi. Nilai b yang merupakan konstanta adalah nilai pangkat yang menunjukkan pola pertumbuhan ikan. Hubungan ini juga memungkinkan untuk membandingkan individu dalam satu populasi maupun antar populasi (Lagler et al. 1977). Nilai b=3 menggambarkan pertumbuhan isometrik, yang akan mencirikan ikan mempunyai bentuk tubuh yang tidak berubah (Ricker 1975) atau pertambahan panjang ikan seimbang dengan pertambahan beratnya. Nilai b ≠ 3 menggambarkan pertumbuhan allometrik. Jika b<3 menunjukkan keadaan ikan 8 9 yang kurus dimana pertambahan panjangnya lebih cepat dari pertambahan beratnya. Jika b>3 menunjukkan pertumbuhan lebih cepat dari pertumbuhan panjangnya (Effendie 1997). 2.6. Kondisi Wilayah Kepulauan Seribu Topografi Perairan Kepulauan Seribu rata‐rata landai (0‐15% dengan ketinggian 0‐2 meter di bawah permukaan laut). Luas daratan masing‐masing pulau dipengaruhi oleh adanya pasang surut yang mencapai 1‐15 meter di atas Pelabuhan Tanjung Priok. Pada umumnya keadaan geologi di Kepulauan Seribu terbentuk dari batuan kapur, karang/pasir, dan sedimen yang berasal dari Pulau Jawa dan Laut Jawa, terdiri dari susunan bebatuan malihan/metamorfosa dan batuan beku, di atas batuan dasar diendapkan sedimen epiklastik, batu gamping, batu lempung yang menjadi dasar pertumbuhan gamping terumbu Kepulauan Seribu (www.kepulauanseribu.net). Secara umum keadaan laut di wilayah Kepulauan Seribu mempunyai kedalaman yang berbeda‐beda, yaitu berkisar antara 0‐40 meter. Di Kepulauan Seribu tidak terdapat sumber hidrologi permukaan, seperti sungai, dan mata air. Kondisi air tanah di wilayah Kepulauan Seribu sangat tergantung dengan kepadatan vegetasinya. Pulau‐ pulau yang mempunyai vegetasi padat dan mempunyai lapisan tanah yang cukup tebal, maka kondisi air tanah akan mempunyai kualitas air tawar yang baik. Hal tersebut karena vegetasi dan lapisan tanah tersebut dapat menyimpan air tanah yang berasal dari hujan (www.kepulauanseribu.net). Keadaan angin di Kepulauan Seribu sangat dipengaruhi oleh angin monsoon yang secara garis besar dapat dibagi menjadi angin musim barat (Desember‐Maret) dan angin musim timur (Juni‐September). Musim pancaroba terjadi antara bulan April‐Mei dan Oktober‐November. Kecepatan angin pada musim barat bervariasi antara 7‐20 knot, biasanya terjadi pada bulan Desember‐Februari. Pada musim timur kecepatan angin berkisar antara 7‐15 knot yang bertiup dari arah Timur Laut sampai tenggara (www.kepulauanseribu.net). Musim hujan di Kepulauan Seribu biasanya terjadi antara bulan November‐April dengan hari hujan antar 10‐20 hari/bulan. Curah hujan terbesar terjadi pada bulan Januari. Musim kemarau terkadang juga terdapat hujan dengan jumlah hari pada saat hujan berkisar antara 4‐10 hari perbulannya. Biasanya curah hujan terkecil terjadi pada bulan Agustus. Curah hujan tahun 2008 tercatat mencapai 169,4 mm sedangkan pada saat bulan‐bulan kering yaitu bulan Juni sampai dengan bulan September. Curah 9 10 hujan bermusim yang dominan di wilayah Kepulauan Seribu yaitu musim barat (musim angin barat disertai hujan lebat) dan musim timur (musim angin timur serta kering). Musim‐musim tersebut mempunyai pengaruh besar bagi kehidupan penduduk maupun bagi kegiatan‐kegiatan lainnya serta kondisi wilayah. Hal tersebut mempengaruhi kegiatan nelayan yang akan sangat terganggu pada saat musim angin barat (www.kepulauanseribu.net). Tipe iklimnya adalah tropika panas dengan suhu rata‐rata berkisar antara 26,5°‐ 28,5°C, sedangkan suhu permukaan air pada saat musim barat berkisar antara 28,5°‐ 30°C dan musim timur suhu permukaan berkisar antara 28,5°‐31°C. Salinitas permukaan berkisar antara 30‐34‰ baik pada musim barat dan musim timur, serta arus permukaan berkecepatan maksimum 0,5 m/s pada musim barat dan musim timur (Pemprov DKI Jakarta 2008). 2.7. Perikanan Tangkap di Kepulauan Seribu Penangkapan ikan di Kepulauan Seribu merupakan salah satu mata pencarian utama nelayan setempat. Produksi perikanan laut untuk tahun 2004 di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dapat mencapai 2.838,80 ton per tahun. Jumlah nelayan hingga tahun 2004 telah mencapai 10.402 orang dengan jumlah tangkapan mencapai 2.838,80 ton. Umumnya nelayan lokal masih memiliki tingkat keterampilan yang terbatas dan aktifitasnya bersifat satu hari melaut, hal ini disebabkan oleh karena terbatasnya teknologi penangkapan baik dalam pengertian alat penangkapannya maupun armada penangkapan ikan yang tidak memadai (Dinas Perternakan, Perikanan, dan Kelautan Propinsi DKI Jakarta 2007b). Menurut Dinas Perternakan, Perikanan, dan Kelautan Propinsi DKI Jakarta (2007b) total armada penangkapan ikan yang ada di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah 1.269 buah dengan jumlah kapal motor sebanyak 899 buah dan yang lainnya seperti motor tempel, perahu layar dan sampan/jukung sebanyak 370 buah. Dukungan terhadap usaha penangkapan ikan ini adalah tersedianya kapal penangkap ikan dengan kapasitas 5 – 10 GT dengan perlengkapan penangkapan yang cukup memadai. Jenis ikan yang tertangkap di perairan sekitar Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu disajikan pada Lampiran 3. 10 11 2.8. Musim Penangkapan Ikan di Kepulauan Seribu Penangkapan ikan ekor kuning dapat dilakukan sepanjang tahun, namun karena fenomena dan kondisi alam tertentu maka kelimpahan hasil tangkapan antara satu musim dengan musim lainnya sangat berbeda. Pada musim barat, angin cenderung bertiup kencang dan banyak uap air, sehingga kondisi perairan di Kepulauan Seribu dan sekitarnya bergelombang besar serta sering disertai hujan. Umumnya pada musim ini para nelayan cenderung untuk mengurangi aktifitas penangkapan ikan dan musim ini dikenal dengan musim paceklik. Sebaliknya pada musim timur, angin bertiup relatif lemah dan udara yang relatif kering sehingga pada musim ini kondisi perairan relatif tenang. Pada musim ini para nelayan kembali meningkatkan aktivitas penangkapan. Perbedaan jumlah upaya (effort) antar musim penangkapan dengan musim paceklik memiliki pengaruh yang tidak dapat diabaikan sehingga dalam menganalisis hasil tangkapan diperlukan informasi hari aktif nelayan melaut setiap bulannya (Dinas Perternakan, Perikanan, dan Kelautan Propinsi DKI Jakarta 2007b). 2.9. Tangkapan Per Satuan Upaya (TPSU) Tangkapan per satuan upaya merupakan jumlah atau bobot hasil tangkap yang diperoleh dari satuan alat tangkap atau dalam waktu tertentu, yang merupakan indeks kelimpahan suatu stok ikan (UU No. 31 tahun 2004). Tangkapan per satuan upaya dipengaruhi oleh satuan waktu, besarnya stok, kegiatan penangkapan, dan kondisi lingkungan di daerah penangkapan ikan. Apabila satuan waktu yang digunakan adalah tahun, perubahan kondisi lingkungan perairan dalam satu tahun tertentu memiliki kecenderungan pola yang sama pada tahun‐tahun berikutnya (Damayanti 2007). Dengan demikian tangkapan per satuan upaya tahunan dipengaruhi oleh besarnya stok dan kegiatan penangkapan yang biasanya dinyatakan dalam bentuk upaya tangkap. Oleh karena itu, kajian tangkapan per satuan upaya dapat memberikan petunjuk perubahan stok akibat kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan tersebut (Damayanti 2007). 2.10. Strategi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Menurut FAO (1997) in Widodo & Suadi (2006), pengelolaan perikanan adalah proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya dan implementasi dari aturan‐ aturan main dibidang ikan dalam rangka menjamin kelangsungan produktivitas 11 12 sumber, dan pencapaian tujuan perikanan lainnya. Pengelolaan sumberdaya perikanan saat ini menuntut perhatian penuh dikarenakan oleh semakin meningkatnya tekanan eksploitasi terhadap berbagai stok ikan (Widodo & Suadi 2006). Tujuan utama pengelolaan perikanan adalah untuk menjamin produksi yang berkelanjutan dari waktu ke waktu dari berbagai stok ikan (resource conservation), terutama melalui berbagai tindakan pengaturan (regulations) dan pengkayaan (enhancement) yang meningkatkan kehidupan sosial nelayan dan sukses ekonomi bagi industri yang didasarkan pada stok ikan (Widodo 2002). Pengelolaan sumberdaya perikanan berdasarkan kriteria sumberdaya dapat dilakukan dengan cara penetapan musim atau penutupan daerah penangkapan secara sementara untuk membatasi ukuran dan umur ketika ditangkap. Penutupan musim harus didasarkan atas bukti‐bukti ilmiah yang dapat membuktikan kondisi umum yang terjadi dan pendekatan penetapan jumlah kapal, kuota untuk membatasi jumlah upaya penangkapan serta jumlah ikan yang ditangkap. Langkah implementasi tersebut dapat ditempuh melalui : (1) pengelolaan sumberdaya dengan penetapan pajak; (2) subsidi; (3) pembatasan impor; dan (4) promosi ekspor. Menurut Satria (2001), ada dua kategori sistem pengelolaan penangkapan ikan, yaitu: (1) Pembatasan input yang terdiri atas jumlah pelaku, jumlah dan jenis kapal, serta jenis alat tangkap, (2) Pembatasan output, dalam hal pembatasan jumlah tangkapan bagi setiap pelaku berdasarkan kuota Pengelolaan sumberdaya alam dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu pengelolaan berbasis pemerintah dan pengelolaan berbasis masyarakat. Kedua pendekatan tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan masing‐masing. Gabungan dari kedua pendekatan tersebut disebut co management (Ditjen Bangda 1999). Co­management adalah pembagian peran, tanggung jawab serta wewenang antara pemerintah dan pengguna sumberdaya perikanan di dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan. Konsep co management diperlukan untuk menambah keberhasilan manajemen sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dan partisipasi pemegang kepentingan (Pomeroy and Williamns 1994 in Nikijuluw 2002). Selain itu yaitu Beddington dan Retting (1983) in Nikijuluw (2002) berpendapat bahwa kegagalan pengelolaan sumberdaya perikanan adalah strategi pendekatan yang bersifat parsial atau hanya tertuju pada strategi tertentu. Menurutnya, pengelolaan harus dilakukan secara menyeluruh dengan mengimplementasikan beberapa 12 13 pendekatan. Pilihan manajemen perikanan sangat tergantung pada kekhasan, situasi, dan kondisi perikanan yang dikelola serta pengelolaannya (Nikijuluw 2002). 13 14 3. METODE PENELITIAN 3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Pengambilan data primer berupa pengukuran panjang dan berat ikan contoh yang ditangkap di perairan Kepulauan Seribu dan didaratkan di PPI Pulau Pramuka dilakukan mulai tanggal 28 Maret sampai 26 Mei 2009 dengan interval waktu pengambilan setiap bulan. Selanjutnya, pengumpulan data sekunder dilaksanakan dari bulan Februari sampai Juni 2009. Fokus utama penelitian adalah para nelayan yang menangkap ikan ekor kuning di Perairan Kepulauan Seribu (Lampiran 4) dengan menggunakan alat tangkap yang dominan yaitu muroami di daerah sekitarnya dan mendaratkan hasil tangkapannya di PPI Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Dasar pertimbangan pemilihan PPI Pulau Pramuka sebagai lokasi penelitian karena PPI tersebut merupakan satu‐satunya Pangkalan Pendaratan Ikan yang berlokasi di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu sehingga diharapkan informasinya dapat mewakili dan mencerminkan upaya pengelolaan sumberdaya ikan ekor kuning di perairan Kepulauan Seribu dan sekitarnya. 3.2. Alat dan Bahan Alat yang digunakan antara lain penggaris 30 cm dengan ketelitian 0,1 cm, timbangan berkapasitas 2000 gram dengan ketelitian 0,5 gram, kamera digital, alat tulis. Bahan yang digunakan antara lain peta lokasi penelitian, data sheet, formulir kuisioner, dokumen‐dokumen, dan literatur yang mendukung penelitian (Lampiran 5). 3.3. Pengumpulan Data Jenis data yang dikumpulkan untuk keperluan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari pengambilan ikan contoh dan wawancara terhadap nelayan berdasarkan kuisioner (Lampiran 6), sedangkan data sekunder terdiri dari data hasil tangkapan dan upaya tangkap beberapa tahun terakhir, dokumen atau literatur yang mendukung penelitian. Ikan contoh ditangkap dengan jaring muroami yang terdiri dari tiga bagian yaitu: mulut, badan, dan kantong. Ukuran mata jaring yang digunakan pada bagian mulut sebesar 3 inchi (7,62 cm), bagian badan 14 15 sebesar 1 ¾ inchi (4,45 cm), dan bagian kantong sebesar 1 inchi (2,54 cm). Dari 13 jumlah nelayan muroami, ikan contoh yang diambil berasal hanya dari satu nelayan saja yang mendarat di PPI Pulau Pramuka dengan dasar pertimbangan mengambil 10% dari total jumlah nelayan muroami yang ada. Nelayan yang terpilih dilakukan secara acak dengan menggunakan metode penarikan contoh acak sederhana (simple random sampling). Ikan contoh diidentifikasi dengan cara mengamati morfologi ikan, yakni bentuk tubuh, sirip pektoral, sirip dorsal, sirip ventral, sirip anal, sirip ekor, warna, dan ciri khusus lainnya. Pengambilan contoh ikan dilakukan dengan metode penarikan contoh berlapis (stratified random sampling) adalah penarikan contoh yang dilakukan dengan cara populasi dibagi menjadi beberapa lapisan berdasarkan karakteristiknya. Ikan contoh dibedakan berdasarkan ukurannya yaitu kecil (6‐12 cm), sedang (13‐20 cm), dan besar (>20 cm). Total ikan contoh yang diambil sebanyak 150 ekor setiap bulan. Ikan contoh kemudian diukur panjang dan berat. Panjang ikan yang diukur adalah panjang total yaitu panjang ikan dari ujung mulut terdepan sampai dengan ujung sirip ekornya. Ikan yang telah diukur panjangnya langsung dipisahkan untuk dilakukan pengukuran berat. Pengambilan contoh responden dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling atau pemilihan responden dengan sengaja berdasarkan kesediaan anggota populasi. Menurut Sulistyo & Basuki (2006), metode pengambilan contoh secara purposive (purposive sampling) adalah penarikan contoh yang dilakukan berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Pengambilan contoh dilakukan terhadap nelayan yang dianggap mewakili sifat‐sifat dari keseluruhan nelayan yang menangkap ikan ekor kuning di Perairan Kepulauan Seribu. Pengambilan contoh responden difokuskan pada satu jenis alat tangkap yaitu muroami. Jenis data yang dikumpulkan melalui kuisioner adalah sebagai berikut : (1) Jenis, ukuran, komposisi dan produksi ikan; seluruh jenis ikan yang tergolong dalam kategori ikan karang konsumsi akan dikumpulkan pada lokasi studi yang telah ditetapkan. Namun, dari seluruh ikan karang konsumsi tersebut akan difokuskan pada ikan ekor kuning. (2) Jumlah dan kategori (tipe) kapal ikan; seluruh kapal yang menangkap ikan di wilayah perairan tersebut akan mendaratkan ikannya di PPI. (3) Alat tangkap; jenis data ini meliputi jenis, kategori dan jumlah alat tangkap yang beroperasi. 15 16 (4) Lokasi penangkapan; karena setiap ikan memiliki lokasi penangkapan (fishing ground) yang berbeda‐beda, oleh karena itu akan dilakukan inventarisasi lokasi penangkapan setiap ikan yang didaratkan. (5) Musim penangkapan; data ini meliputi waktu‐waktu penangkapan ikan laut, yaitu musim panen dan paceklik. (6) Nelayan; data nelayan yang relevan untuk dikumpulkan meliputi jumlah dan kategori nelayan. Data sekunder dapat didapatkan dari instansi terkait, baik yang ada di lokasi penelitian maupun yang ada di Jakarta. Beberapa instansi yang dijadikan sumber bagi data sekunder antara lain : Suku Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan DKI Jakarta; Suku Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; Pangkalan Pendaratan Ikan Pulau Pramuka; dan Balai Konservasi Sumberdaya Alam. Jenis data yang diperlukan adalah: (1) Produksi (penangkapan) (2) Upaya/frekuensi lama/jumlah penangkapan (3) Sarana usaha perikanan (kapal, alat tangkap, dll) (4) Pemasaran (bentuk komoditas, tujuan, sistem pemasaran) 3.4. Analisis Data 3.4.1. Sebaran frekuensi panjang Sebaran frekuensi panjang adalah distribusi ukuran panjang pada kelompok panjang tertentu. Sebaran frekuensi panjang didapatkan dengan menentukan selang kelas, nilai tengah kelas, dan frekuensi dalam setiap kelompok panjang. Dalam penelitian ini, untuk menganalisis sebaran frekuensi panjang menggunakan tahapan‐ tahapan sebagai berikut : (1) Menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari seluruh data panjang total ikan ekor kuning. (2) Dengan melihat hasil pengamatan frekuensi pada setiap selang kelas panjang ikan ditetapkan jumlah kelas sebanyak 22 kelas dengan interval sebesar 10 mm. (3) Menentukan limit bawah kelas bagi selang kelas yang pertama dan kemudian limit atas kelasnya. Limit atas didapatkan dengan cara menambahkan lebar kelas pada limit bawah kelas. (4) Mendaftarkan semua limit kelas untuk setiap selang kelas. 16 17 (5) Menentukan nilai tengah kelas bagi masing‐masing kelas dengan merata‐ratakan limit kelas. (6) Menetukan frekuensi bagi masing‐masing kelas. Sebaran frekuensi panjang yang telah ditentukan dalam masing‐masing kelas, diplotkan dalam sebuah grafik untuk melihat jumlah distribusi normalnya. Dari grafik tersebut dapat terlihat jumlah puncak yang menggambarkan jumlah kelompok umur (kohort) yang ada. Dapat terlihat juga pergeseran distribusi kelas panjang setiap bulannya. Pergeseran sebaran frekuensi panjang menggambarkan jumlah kelompok umur (kohort) yang ada. Bila terjadi pergeseran modus sebaran frekuensi panjang berarti terdapat lebih dari satu kohort. Bila terdapat lebih dari satu kohort, maka dilakuakn pemisahan distribusi normal. Menurut Sparre dan Venema (1999), metode yang dapat digunakan untuk memisahkan distribusi komposit ke dalam distribusi normal adalah metode Bhattacharya (1967) in Sparre dan Venema (1999) dengan bantuan software program FISAT II. 3.4.2. Parameter pertumbuhan (L∞, K) dan t0 Plot Ford‐Walford merupakan salah satu metode paling sederhana dalam menduga persamaan pertumbuhan Von Bertalanffy dengan interval waktu pengambilan contoh yang sama (Sparre dan Venema 1999). Persamaan pertumbuhan Von Bertalanffy dapat dinyatakan sebagai berikut : (1) Lt adalah panjang ikan pada saat umur t (satuan waktu), L∞ adalah panjang maksimum secara teoritis (panjang asimtotik), K adalah koefisien pertumbuhan (per satuan waktu), t0 adalah umur teoritis pada saat panjang sama dengan nol. Untuk t0 sama dengan nol, persamaan (1) dapat ditulis menjadi : (2) sehingga (3) Untuk t sama dengan t+1 dan t sama dengan t, persamaan (2) bagi Lt+1‐Lt menjadi : (4) sehingga 17 18 (5) Substitusikan persamaan (3) ke persamaan (5) diperoleh : (6) sehingga (7) Lt dan Lt+1 merupakan panjang ikan pada saat t dan panjang ikan yang dipisahkan oleh interval waktu yang konstan (1=tahun, bulan, atau minggu) (Pauly 1984). Persamaan (7) dapat diduga dengan persamaan regresi linear dan jika Lt sebagai absis diplotkan terhadap Lt+1 sebagai ordinat maka garis lurus yang dibentuk akan memiliki kemiringan (slope) sama dengan dan titik potong dengan absis sama dengan Dengan demikian, nilai K dan L∞ diperoleh dengan cara sebagai berikut : (8) (9) Umur teoritis ikan pada saat panjang sama dengan nol dapat diduga secara terpisah menggunakan persamaan empiris Pauly (Pauly 1983) : (10) 3.4.3. Hubungan panjang berat Hubungan panjang berat digambarkan dalam dua bentuk yaitu isometrik dan alometrik (Hile 1936 in Effendie 1997). Untuk kedua pola ini berlaku persamaan : W = a L b (11) Jika dilinearkan melalui transformasi logaritma, maka diperoleh persamaan : Log W = Log a + b Log L (12) Untuk mendapatkan parameter a dan b, digunakan analisis regresi linier sederhana dengan Log W sebagai ’y’ dan Log L sebagai ’x’. 18 19 Untuk menguji nilai b=3 atau b ≠ 3 (b>3, pertambahan berat lebih cepat dari pada pertambahan panjang) atau (b<3, pertambahan panjang lebih cepat dari pada pertambahan berat) dilakukan uji‐t (Sukimin et al. 2006), dengan hipotesis : H0 : β = 3, hubungan panjang dengan berat adalah isometrik H1 : β ≠ 3, hubungan panjang dengan berat adalah allometrik Allometrik positif, jika b>3 (pertambahan berat lebih dari pada pertambahan panjang) dan allometrik negatif, jika b<3 (pertambahan panjang lebih cepat dari pada pertambahan berat). thitung = b1 − b0 Sb1 (13) b1 adalah nilai b (hubungan dari panjang berat), b0 adalah 3, dan Sb1 adalah simpangan koefisien b. Selanjutnya, nilai thitung dibandingkan dengan nilai ttabel pada selang kepercayaan 95%. Kemudian untuk mengetahui pola pertumbuhan ikan, kaidah keputusan yang diambil mengacu pada Nasoetion & Barizi (1980) yaitu : jika thitung > ttabel maka tolak hipotesis nol (H0) dan jika thitung < ttabel maka gagal tolak hipotesis nol (H0). 3.4.4. Tangkapan per satuan upaya Data hasil upaya penangkapan ikan ekor kuning dapat dianalisis dengan menghitung nilai hasil tangkapan per upaya penangkapan atau analisis tangkapan per satuan upaya. TPSU digunakan sebagai indeks kelimpahan sumberdaya perikanan. TPSU dihitung dengan rumus sebagai berikut : ⎡T ⎤ ⎥ ⎣U ⎦ TPSU= ⎢ (14) TPSU adalah jumlah tangkapan per satuan upaya, T adalah jumlah tangkapan bulanan harian, atau tahunan ikan ekor kuning (kg) dan U adalah merupakan jumlah upaya bulanan, harian, atau tahunan ikan ekor kuning (hari). Selanjutnya TPSU ini disajikan dalam bentuk grafik. 19 20 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Hasil 4.1.1. Wilayah administrasi Kepulauan Seribu Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terletak di sebelah Utara Teluk Jakarta dan Laut Jawa Jakarta. Pulau Sebira terletak sekitar 100 mil dari daratan Teluk Jakarta. Posisi ini bila dikaitkan dengan Jakarta yang tidak lain adalah sebuah kota Bandar, maka Kepulauan Seribu adalah bagian muka dari Jakarta (www.kepulauanseribu.net). Pada separuh teluk bagian barat, terdapat beberapa pulau kecil yang sebagian besar telah dipergunakan sebagai areal permukiman penduduk dan sebagian lainnya dipergunakan sebagai tempat peristirahatan (www.kepulauanseribu.net). Total luas keseluruhan wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu kurang lebih hampir 11 kali luas daratan Jakarta, yaitu luas daratan mencapai 897,71 ha dan luas perairan Kepulauan Seribu mencapai 6.997,50 km2 (www.kepulauanseribu.net). Jumlah keseluruhan pulau yang ada di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mencapai 110 buah. Adapun Komposisinya adalah : (1) 50 Pulau mempunyai luas kurang dari 5 ha (2) 26 Pulau mempunyai luas antara 5‐10 ha (3) 24 Pulau mempunyai luas lebih dari 10 ha Pulau Pramuka merupakan salah satu pulau yang berada pada gugusan Kepulauan Seribu. Lokasi terbentang dari kawasan Teluk Jakarta sampai Pulau Sebira (www.kepulauanseribu.net). Pulau ini merupakan pusat administrasi dan pemerintahan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu. Pulau Pramuka termasuk ke dalam Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kelurahan Pulau Panggang. Pulau Pramuka diperuntukkan sebagai ibukota dari Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu. Pulau ini terdiri dari 2 kecamatan yakni Kepulauan Seribu Utara dan Kepulauan Seribu Selatan, 6 kelurahan, 24 RW, 119 RT. Kepulauan Seribu dilalui jalur pelayaran kapal‐kapal besar dan merupakan muara sungai (daerah belakang) dari daerah‐daerah di bagian selatannya (www.wikipedia.org). Luas Pulau Pramuka sekitar 16 ha, terdapat sarana pelestarian penyu sisik yang saat ini jumlahnya sudah sedikit sehingga dilindungi. Pulau ini juga diperuntukkan sebagai pemukiman penduduk. Jumlah penduduknya sekitar 1.004 jiwa 20 21 (www.kepulauanseribu.net). Masyarakat yang mendiami Pulau Pramuka sebagian besar berasal dari Bugis, Tangerang, dan Jakarta. Tata tempat tinggal dan sanitasi Pulau Pramuka cukup baik, sedangkan dalam bidang pendidikan sudah terdapat sekolah dari SD hingga SMA. Sarana dan prasarana cukup memadai mulai dari masjid, rumah sakit, sekolah, dermaga, PPI, villa, dan penginapan bagi pengunjung wisata. Transportasi akses untuk menuju pulau tersebut dapat dicapai melalui akses langsung dari darat melalui Muara Angke dan Pantai Marina Ancol (www.wikipedia.org). Wilayah Administrasi Kepulauan Seribu secara ringkas disajikan pada Tabel 1. Tabel 1. Letak geografis Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Letak Geografis Uraian 1. Letak Kepulauan Seribu 2. Luas Wilayah 3. Letak di Atas Permukaan Laut 4. Batas Wilayah 4.1. Utara 4.2. Timur 4.3. Barat Utara : 05°10"00' ‐ 05°10"00' LS 106°19"30' ‐ 106°44"50' BT Timur : 05°10"00' LS 106°19"30' BT Selatan : 05°10"00' ‐ 05°57"00' LS 106°44"50' ‐ 106°44"50' BT Barat : 05°10"00' LS 106°44"50' BT 8,70 km² 1 (satu) meter Laut Jawa Laut Jawa Wilayah Provinsi Lampung dan Laut Jawa Wilayah Kota Jakarta Utara, wilayah Provinsi Banten, dan Wilayah Provinsi Jawa Barat 4.4. Selatan Sumber : BPS (2008) 4.1.2. Fasilitas yang tersedia di PPI Pulau Pramuka PPI Pulau Pramuka dengan luas 2.000 m2 terletak di Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dengan batas lokasi sebagai berikut : Utara : Resort (Milik perorangan yang dikelola oleh Bapak Nalim) Selatan : Villa Delima Indah Barat : Perairan Laut Pulau Pramuka Timur : Jalan Lingkungan (Rumah Dinas Bupati) 21 22 Adapun skema PPI disajikan pada Lampiran 7. Sebagai sarana untuk melakukan kegiatan pelelangan ikan telah ada bangunan seluas 438,46 m2 dengan dilengkapi beberapa sarana penunjang yaitu timbangan, trays, cool box, mesin pemecah es, dan mesin penyemprot lantai. Beberapa kegiatan yang dilakukan di PPI ini antara lain adalah proses pembongkaran yang meliputi kegiatan handling dan penyortiran. Penyortiran ini dilakukan untuk memisahkan antara ikan kecil dan ikan besar, memisahkan antara berbagai jenis ikan dan juga untuk memilih ikan yang masih dalam kondisi bagus untuk dikirim ke Muara Angke. Peralatan yang digunakan dalam proses ini antara lain adalah : (1) Timbangan 2 unit (2) Cool box 12 unit (3) Keranjang (trays) 7 unit Sejak dibangun pada tahun 1997 sampai tahun 2005 relatif tidak ada aktivitas bongkar muat ikan. Pada tahun 2006 dilakukan uji coba, tetapi tidak berlanjut karena berbagai kendala. Kegiatan pendaratan ikan dimulai kembali pada bulan Mei 2007 dan berlangsung secara kontinu sampai sekarang. Selain PPI terdapat juga gedung pertemuan PPI Pulau Pramuka yang sering digunakan oleh Suku Dinas Perikanan setempat untuk melakukan pertemuan. Tersedia juga tempat peminjaman peralatan selam (dive shop) untuk menunjang kegiatan lainnya, adanya sarana pusat informasi, sarana gudang es yang digunakan untuk menyimpan balok‐balok es sebagai pengawet ikan, docking kapal sebagai sarana untuk perbaikan armada kapal‐kapal (Lampiran 8). Sebagian kecil ikan yang didaratkan di PPI dikonsumsi oleh warga Pulau Pramuka sedangkan yang lainnya diangkut oleh pemilik untuk dijual ke Muara Angke. Kegiatan di PPI juga belum terlihat adanya pelelangan, tetapi hanya ada pendaratan, penimbangan, pencatatan, dan penyimpanan. Setelah itu dilakukan pengkapalan kembali untuk diangkut ke Muara Angke dan aktivitas di PPI belum juga memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. 4.1.3. Sebaran frekuensi panjang ikan ekor kuning Ikan ekor kuning yang diamati selama penelitian berjumlah 450 ekor masing‐ masing 150 ekor pada bulan Maret, April, dan Mei. Panjang minimum dan panjang maksimum ikan ekor kuning adalah 75 mm dan 294 mm. Pada bulan Maret frekuensi ikan ekor kuning jantan dan betina adalah 125‐134 mm dan 135‐144 mm. Pada bulan 22 23 April frekuensi ikan ekor kuning jantan dan betina adalah 125‐134 mm dan 135‐144 mm. Pada bulan Mei frekuensi ikan ekor kuning jantan dan betina adalah 115‐124 mm dan 125‐134 mm. Secara keseluruhan diketahui bahwa frekuensi tertinggi ikan ekor kuning jantan dan betina adalah 125‐134 mm (Gambar 2). Hasil ini menunjukkan bahwa ukuran ikan ekor kuning betina lebih besar dibandingkan ukuran ikan ekor kuning jantan. MARET N =150 (a) APRIL N =150 (b) Gambar 2. Sebaran frekuensi panjang ikan ekor kuning setiap kelas (a) bulan Maret, (b) bulan April, (c) bulan Mei, (d) secara total 23 24 MEI N =150 (c) TOTAL N =450 (d) Gambar 2. (lanjutan) 4.1.4. Parameter pertumbuhan (L∞, K) dan t0 Parameter pertumbuhan Von Bertalanffy (K dan L∞) diduga dengan menggunakan metode Plot Ford‐Walford. Metode Ford Walford dapat digunakan karena data diambil pada interval waktu yang tetap yaitu satu bulan selama tiga bulan. Hasil pemisahan kelompok ukuran menunjukkan bahwa ikan contoh terdiri dari beberapa kelompok ukuran seperti ditampilkan pada Gambar 3 : 24 25 Umur x JANTAN Umur x+1 Umur x+2 (a) BETINA Umur x Umur x+1 Umur x+2 Umur x+3 (b) TOTAL Umur x+1 Umur x+2 Umur x Umur x+3 Umur x+4 (c) Gambar 3. Kelompok ukuran ikan ekor kuning (a) jantan, (b) betina, (c) secara total Hasil analisis kelompok ukuran ikan di atas memiliki panjang rata‐rata, jumlah populasi dan indeks separasi seperti disajikan pada Tabel 2, Tabel 3, dan Tabel 4. Dalam pemisahan kelompok ukuran ikan dengan menggunakan metode Bhattacharya indeks separasi (separation index, SI) sangat penting untuk diperhatikan. Menurut Hasselblad (1969), McNew & Summerflat (1978), dan Clark (1981) in Sparre dan 25 26 Venema (1999), jika nilai I<2 maka pemisahan kelompok ukuran tidak mungkin dilakukan karena terjadi tumpang tindih yang besar antar kelompok ukuran ikan. Nilai simpangan baku yang semakin besar menunjukkan bahwa ikan yang semakin tua mempunyai ukuran yang semakin beragam. Tabel 2. Hasil analisis masing‐masing kelompok ukuran ikan ekor kuning jantan L(t) Jumlah populasi (N) Standar deviasi (S) Indeks separasi (I) (1) 128,38 232 14,35 ‐ (2) 158,73 77 15,28 2,07 (3) 216,31 60 22,66 2,28 Total 369 Tabel 3. Hasil analisis masing‐masing kelompok ukuran ikan ekor kuning betina L(t) Jumlah populasi (N) Standar deviasi (S) Indeks separasi (I) (1) 125,77 63 8,03 ‐ (2) 159,89 27 9,26 2,25 (3) 193,67 23 9,84 2,19 (4) 240,80 14 11,09 2,27 (5) 265,01 7 12,58 2,00 Total 134 Tabel 4. Hasil analisis masing‐masing kelompok ukuran ikan ekor kuning secara total L(t) (1) 84,50 Jumlah populasi (N) Standar deviasi (S) Indeks separasi (I) 8 9,54 ‐ (2) 127,11 152 10,35 3,05 (3) 167,43 139 13,41 3,88 (4) 203,41 26 13,61 3,34 (5) 246,59 17 14,69 4,59 Total 342 Pada Tabel 5 disajikan parameter pertumbuhan L∞ dan K dan (metode Ford‐ Walford) dan umur teoritis saat panjang ikan sama dengan nol (t0): 26 27 Tabel 5. Parameter pertumbuhan (L∞, K) dan t0 Contoh ikan Jantan Betina Total K (per tahun) 0,55 0,19 0,35 Parameter pertumbuhan L∞ (mm) 303,00 303,98 303,28 t0 (tahun) ‐0,0793 ‐0,2389 ‐0,1268 4.1.5. Pertumbuhan Persamaan pertumbuhan Von Bertalanffy ikan ekor kuning jantan dan betina masing‐masing adalah Lt = 303,00 (1‐e‐0,55(t+0,0793)) dan Lt = 303,98 (1‐e‐0,19(t+0,2389)) sedangkan persamaan pertumbuhan Von Bertalanffy ikan ekor kuning secara total adalah Lt = 303,28 (1‐e‐0,35(t+0,1268)). Ikan dengan nilai K kecil umurnya relatif panjang. Dari hasil parameter pertumbuhan yang didapatkan terlihat bahwa ada perbedaan antara ikan ekor kuning jantan dengan ikan ekor kuning betina. Perbedaannya terletak pada nilai koefisien pertumbuhan (K) dan nilai t0 yang dapat mempengaruhi besarnya panjang pertama kali ikan tersebut lahir (L t0). Ikan jantan biasanya nilai mempunyai nilai K yang lebih besar daripada ikan betina. Perbedaan laju pertumbuhan ikan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal yang terdiri dari (a) faktor genetik yang secara langsung membatasi ukuran maksimum ikan, dan (b) ukuran tubuh ikan. Jika laju pertumbuhan kecil maka ukuran tubuh ikan akan meningkat (Wooton 1990; Pauly 1994 in Welcomme 2001). Oleh karena itu faktor internal yang menyebabkan nilai K pada ikan ekor kuning lebih kecil adalah faktor genetik karena perbedaan spesies dan faktor ukuran ikan ekor kuning yang relatif besar. Pada Gambar 4 disajikan kurva pertumbuhan ikan ekor kuning dengan memplotkan umur (tahun) dan panjang teoritis (mm). 4.1.6. Hubungan panjang berat Contoh ikan ekor kuning secara total adalah sebanyak 450 ekor yang terdiri dari 289 ekor ikan betina dan 161 ekor ikan jantan. Dalam menghitung hubungan panjang berat sebaiknya dipisahkan antara ikan jantan dengan ikan betina, karena biasanya terdapat perbedaan hasil antara kedua jenis kelamin tersebut. Pola pertumbuhan berdasarkan hubungan panjang berat ikan ekor kuning jantan dan betina di Perairan Kepulauan Seribu disajikan pada Tabel 6 : 27 28 Lt = 303(1‐e(‐0,55(t+0,0793)) (a) Lt = 303,98(1‐e(‐0,19(t+0,2389)) (b) Lt = 303,28(1‐e(‐0,35(t+0,1268)) (c) Gambar 4. Kurva pertumbuhan ikan ekor kuning (a) jantan, (b) betina, (c) secara total 28 29 Tabel 6. Hasil perhitungan panjang dan berat ikan ekor kuning Pola pertumbuhan (setelah dilakukan uji t dengan α=0,05) Contoh ikan N a Jantan 289 ‐3,765 2,579 0,872 W = 0,00017 L 2,579 Allometrik negatif Betina 161 ‐5,164 3,242 0,864 W = 0,000006 L 3,242 Allometrik positif Total 450 ‐4,684 b R² 3,009 0,853 W = aLb W = 0,00002 L 3,009 Isometrik Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan panjang berat pada ikan ekor kuning memiliki korelasi yang sangat erat. Hal ini berdasarkan nilai koefisien korelasi (r) yang mendekati satu. Secara umum nilai b ikan ekor kuning jantan dan betina berkisar antara 2,579 sampai 3,242 (Gambar 5). Nilai ini berada pada kisaran nilai b pada umumnya yang dikemukakan oleh Lagler et al. (1977) bahwa nilai b berfluktuasi antara 2,5 sampai 4; dan kebanyakan mendekati 3. Hasil analisis menunjukkan bahwa ikan ekor kuning jantan memiliki persamaan hubungan panjang berat W=17x10‐5L2,579(n=289; r= 0,872; α=0,05). Ikan ekor kuning betina memiliki persamaan hubungan panjang berat W=6x10‐6L3,242(n=161; r= 0,864; α=0,05). Hubungan panjang berat ikan ekor kuning secara keseluruhan W=2x10‐5L3,009 (n=450; r=0,853; α=0,05). Selanjutnya menurut Bagenal (1978) faktor‐faktor yang menyebabkan perbedaan nilai b selain perbedaan spesies adalah faktor lingkungan, berbedanya stok ikan dalam spesies yang sama, tahap perkembangan ikan, jenis kelamin, tingkat kematangan gonad, bahkan perbedaan waktu dalam hari karena perubahan isi perut. Moutopoulos dan Stergiou (2002) in Kharat et al. (2008) menambahkan bahwa perbedaan nilai b juga dapat disebabkan oleh perbedaan jumlah dan variasi ukuran ikan yang diamati. Pada Tabel 6, pola pertumbuhan ikan ekor kuning total keseluruhan adalah isometrik, artinya ikan mempunyai bentuk tubuh yang tidak berubah (Ricker 1975) atau pertambahan panjang ikan seimbang dengan pertambahan beratnya. Pola pertumbuhan yang berbeda terlihat pada ikan ekor kuning betina dengan ikan ekor kuning jantan. Penyebabnya diduga karena ukuran ikan betina yang tertangkap lebih beragam, dari ukuran kecil sampai besar sehingga hubungan panjang berat ikan contoh yang diamati menggambarkan keadaan sebenarnya. Hal ini terlihat dari pola pertumbuhan ikan ekor kuning betina adalah allometrik positif sehingga diduga bahwa nilai b>3 pada ikan betina mungkin disebabkan oleh faktor lingkungan, makanan yang lebih banyak, ataupun faktor tingkat kematangan gonad. 29 30 JANTAN y=0,00017x2,579 N=150 (a) BETINA y=7.10­6x3,242 N=150 (b) TOTAL y=2.10­5x3,009 N=150 (c) Gambar 5. Hubungan panjang berat ikan ekor kuning (a) jantan, (b) betina, (c) secara total 30 31 4.1.7. Tangkapan per satuan upaya Data hasil tangkapan dan upaya tangkap didapatkan dari Suku Dinas Perikanan Kepulauan Seribu yang dikumpulkan selama 5 tahun terakhir. Effort yang digunakan dalam perhitungan TPSU yaitu unit kapal yang melakukan penangkapan ikan setiap tahunnya. Kegiatan penangkapan ikan ekor kuning di daerah Kepulauan Seribu mengalami fluktuasi sepanjang tahun. Sejak tahun 2003 hingga saat ini, ikan ekor kuning menjadi salah satu ikan dominan yang tertangkap di daerah Perairan Kepulauan Seribu. Pelaku usaha perikanan ekor kuning terus meningkatkan upayanya dalam pemanfaatan sumberdaya ini demi mendapatkan hasil tangkapan sebanyak‐ banyaknya. Berdasarkan data statistik perikanan (Tabel 7), diketahui bahwa alat tangkap yang digunakan dalam operasi penangkapan ikan ekor kuning secara umum meningkat jumlahnya. Tabel 7. Hasil tangkapan dan upaya tangkap ikan ekor kuning di Kepulauan Seribu Tahun 2003 2004 2005 2006 2007 Hasil Tangkapan Upaya (Ton) (Unit kapal) 411 70 441 75 557 75 621 75 673 77 TPSU (Ton/Unit kapal) 5,87 5,88 7,43 8,28 8,74 Sumber : Suku Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (2009) Hasil tangkapan per upaya terendah terjadi pada tahun 2003 adalah 5,78 ton/unit kapal, sedangakan hasil tangkapan upaya tertinggi terjadi pada tahun 2005 adalah 8,74 ton/unit kapal (Gambar 6). Peningkatan produksi terjadi seiring dengan adanya peningkatan upaya penangkapan, namun hasil tangkapan yang dominan adalah ikan yang mempunyai ukuran kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa tekanan penangkapan terhadap sumberdaya ini terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini tentu saja mempengaruhi hasil tangkapan ikan yang diperoleh nelayan dari Perairan Kepulauan Seribu. Beberapa ciri yang dapat menjadi patokan suatu perikanan sedang menuju kondisi upaya tangkap lebih adalah waktu melaut menjadi lebih panjang dari biasanya, lokasi penangkapan menjadi lebih jauh dari biasanya, ukuran mata jaring menjadi lebih kecil dari biasanya, yang kemudian diikuti produktivitas (hasil tangkapan satuan upaya) yang menurun, ukuran ikan yang semakin kecil, dan biaya penangkapan yang 31 32 semakin meningkat (Widodo & Suadi 2006). Gambar 6 dapat menginformasikan bahwa hasil tangkapan meningkat tetapi didominasi oleh ikan‐ikan yang berukuran kecil, hal ini ditandai dengan nilai slope (kemiringan) yang besar dengan peningkatan hasil tangkapan yang rendah kemudian cenderung mendekati kestabilan. Gambar 6. Tangkapan per satuan upaya ikan ekor kuning di Kepulauan Seribu Jumlah tangkapan tertinggi periode bulan Mei 2007‐Maret 2009 terjadi pada bulan Maret 2008 dan jumlah tangkapan terendah terjadi pada bulan Juli 2007. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa nelayan, puncak penangkapan pada musim timur terjadi pada bulan Maret sedangkan pada musim barat terjadi pada bulan November (Gambar 7). Hasil tangkapan muroami pada kedua musim, tertinggi pada bulan Maret dan bulan November. Hasil tangkapan dipengaruhi oleh satuan waktu, besarnya stok, kegiatan penangkapan, dan kondisi di daerah penangkapan (Widodo 2002). Gambar 7. Total tangkapan ikan ekor kuning setiap bulan di Kepulauan Seribu periode Mei 2007‐Maret 2009 32 33 4.2. Pembahasan 4.2.1. Sebaran frekuensi panjang ikan ekor kuning Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran ikan ekor kuning betina lebih besar dibandingkan ukuran ikan ekor kuning jantan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Nikolsky (1963) bahwa biasanya ukuran ikan betina lebih besar beberapa satuan dibandingkan ikan jantan untuk menjamin fekunditas yang besar dalam stok dan perbedaan ukuran ini dicapai melalui ikan jantan yang matang gonad lebih cepat dan jangka hidupnya yang lebih singkat. Menurut Lagler et al. (1977) perbedaan ukuran antar jenis kelamin kemungkinan disebabkan oleh faktor genetik. Ikan berukuran besar dengan jumlah yang sangat sedikit ini diduga adalah induk ikan ekor kuning. Hal ini sesuai dengan pernyataan Lagler et al. (1977) bahwa ukuran terbesar yang muncul pada umumnya berhubungan dengan induk yang paling “penting”. Panjang total maksimum ikan ekor kuning yang tertangkap adalah 294 mm. Menurut Allen et al. (2007) panjang total maksimum mencapai 500 mm. Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh beberapa kemungkinan yaitu perbedaan lokasi pengambilan ikan contoh, keterwakilan contoh yang diambil, dan kemungkinan terjadinya tekanan penangkapan yang tinggi. Spesies yang sama pada lokasi yang berbeda akan memiliki pertumbuhan yang berbeda pula karena perbedaan faktor luar maupun faktor dalam yang mempengaruhi pertumbuhan ikan tersebut. Menurut Effendi (1997) faktor dalam umumnya adalah faktor yang sulit dikontrol seperti keturunan, jenis kelamin, umur, parasit, dan penyakit. Faktor luar yang utama mempengaruhi pertumbuhan ikan yaitu suhu dan makanan. Dengan asumsi bahwa ikan contoh sudah mewakili populasi yang ada maka ukuran panjang total maksimum yang lebih kecil bisa mengindikasikan adanya tekanan penangkapan yang tinggi. Namun untuk menyimpulkan hal ini diperlukan pembandingan dengan spesies dan lokasi yang sama serta kajian lebih lanjut. Kemungkinan terakhir adalah tidak terpilihnya ikan yang lebih besar pada saat pengambilan ikan contoh karena pengacakan. Berdasarkan Gambar 2 terlihat adanya pergeseran sebaran ukuran panjang. Pergeseran pertama dimulai dari sebaran panjang bulan Maret dan April ke sebelah kiri kemudian pada bulan April dan Maret sebaran frekuensi kelas bergeser ke sebelah kiri juga. Hal ini menunjukkan selama bulan Maret sampai Mei terdapat satu kelompok ukuran. Pada bulan Maret, panjang ikan ekor kuning berkisar antara selang kelas 115‐124 mm sampai 225‐234 mm dengan frekuensi tertinggi pada selang 135‐ 144 mm. Pada bulan April, panjang ikan ekor kuning berkisar antara selang kelas 95‐ 33 34 104 mm sanpai 235‐244 mm dengan frekuensi tertinggi pada selang kelas 125‐134 mm dan pada bulan Maret berkisar antara selang kelas 75‐84 mm sampai 285‐294 mm dengan frekuensi terbesar pada selang kelas 115‐124 mm. Pergeseran selang ukuran panjang ikan yang banyak tertangkap ke selang ukuran yang lebih kecil dapat dijadikan sebagai indikasi adanya rekruitmen pada interval waktu pengamatan. Namun untuk menentukan musim pemijahan dan rekruitmen ikan ekor kuning di Kepulauan Seribu perlu dilakukan kajian lebih lanjut. Pergeseran selang ukuran panjang ikan yang banyak tertangkap ke selang ukuran yang lebih besar dapat dijadikan sebagai indikasi adanya pertumbuhan pada interval waktu pengamatan yaitu satu bulan. Dengan adanya pertumbuhan dalam interval waktu yang singkat maka diduga bahwa ikan ekor kuning memiliki laju pertumbuhan yang relatif kecil. Kajian lebih lanjut diperlukan untuk membuktikan dugaan ini dan akan dibahas pada sub bab pertumbuhan. 4.2.2. Parameter pertumbuhan (L∞, K) dan t0 Plot Ford‐Walford merupakan salah satu metode paling sederhana dalam menduga persamaan pertumbuhan Von Bertalanffy dengan interval waktu pengambilan contoh yang sama (Sparre dan Venema 1999). Dari analisis frekuensi panjang didapatkan kelompok umur ikan ekor kuning yang dapat diolah selanjutnya dengan menggunakan metode Ford Walford guna mendapatkan nilai L∞, K, dan t0. Hasil analisis pemisahan kelompok ukuran ikan ekor kuning jantan menunjukkan bahwa jumlah total ikan yang diamati yaitu 368 ekor sedangkan hasil analisis pemisahan kelompok ukuran ikan ekor kuning betina menunjukkan bahwa jumlah total ikan yang diamati yaitu 134 ekor, dan hasil analisis pemisahan kelompok ukuran ikan ekor kuning secara total menunjukkan bahwa jumlah total ikan yang diamati yaitu 342 ekor. Jumlah ini dapat bernilai lebih besar ataupun lebih kecil dibandingkan dengan jumlah ikan contoh yang diobservasi. Perbedaan nilai teoritis dengan nilai observasi disebabkan oleh adanya pengacakan. Meskipun ikan contoh yang digunakan merupakan contoh acak yang sempurna nilai observasi akan tetap mengalami fluktuasi seputar distribusi yang sesungguhnya (distribusi dari populasi) (Sparre dan Venema 1999). Dalam pemisahan kelompok ukuran ikan dengan menggunakan metode Bhattacharya, indeks separasi (separation indeks, SI) sangat penting untuk diper‐ hatikan. Menurut Hasselblad (1969), McNew & Summerflat (1978), dan Clark (1981) 34 35 in Sparre dan Venema (1999), jika nilai I<2 maka pemisahan kelompok ukuran tidak mungkin dilakukan karena terjadi tumpang tindih yang besar antar kelompok ukuran ikan. Berdasarkan hasil pemisahan kelompok ukuran ikan ekor kuning jantan pada Tabel 2 diketahui bahwa nilai indeks separasi antar kelompok ukuran yaitu 2,07 dan 2,28. Pada Tabel 3 diketahui bahwa nilai indeks separasi antar kelompok ukuran ikan ekor kuning betina yaitu 2,25; 2,19; 2,27; dan 2,00. Pada Tabel 4 diketahui bahwa nilai indeks separasi antar kelompok ukuran yaitu 5,05; 3,88; 3,34; dan 4,59. Hal ini menunjukkan bahwa pemisahan kelompok ukuran ikan ekor kuning di atas dapat diterima dan digunakan untuk analisis selanjutnya. 4.2.3. Pertumbuhan Pada Gambar 4 disajikan kurva pertumbuhan ikan ekor kuning dengan memplotkan umur (bulan) dan panjang teoritis (mm) ikan sampai ikan berumur 14 bulan untuk ikan ekor kuning jantan, dan untuk ikan ekor kuning betina berumur sampai 38 bulan. Namun demikian dari data total ikan ekor kuning, umur ikan dapat mencapai umur sampai 23 bulan. Panjang maksimum ikan ekor kuning adalah 294 mm dan panjang asimtotik ikan ekor kuning adalah 303 mm. Kurva pertumbuhan (Gambar 4) menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ikan selama rentang hidupnya tidak sama. Ikan muda memiliki laju pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan ikan tua (mendekati L∞). Walaupun dengan laju pertumbuhan yang kecil, namun ikan tetap akan mengalami pertumbuhan panjang bahkan dalam kondisi faktor lingkungan yang tidak mendukung. Peningkatan ukuran panjang umumnya tetap berlangsung walaupun ikan mungkin dalam keadaan kekurangan makanan (Anderson & Gutreuter 1983 in Busacker et al. 1990). Pertumbuhan memiliki karakteristik tertentu pada masing‐masing kelompok ikan. Pada periode ini variasi yang sangat bergantung pada suplai makanan (Nikolsky 1963). Petumbuhan ikan dan organisme lainnya menurut Pauly (1998) didefinisikan sebagai waktu yang dihabiskan pada daerah pemangsaan yang berbeda dihubungkan dengan ukuran tubuh dan ini merupakan proses kunci dibalik sejarah hidup organisme yang lebih spesifik. Studi pertumbuhan dilakukan untuk melihat koefisien b, yaitu penduga kedekatan hubungan panjang dan berat, apakah isometrik, allometrik positif, atau allometrik negatif (Effendie 1997). Perkiraan pertumbuhan, rekruitmen, dan 35 36 mortalitas merupakan paremeter dasar yang diperlukan untuk menghitung stok suatu populasi ikan. Ketika parameter‐parameter ini digunakan sebagai parameter input pada model hasil tangkapan perikanan, alternatif pengelolaan, dan akibatnya terhadap populasi atau komunitas ikan, seluruh parameter ini dapat digunakan dalam hubungannya dengan perkiraan hasil tangkapan (Wudneh 1998). Parameter pertumbuhan memegang peranan yang sangat penting dalam pengkajian stok ikan dan dalam menyusun rencana pengelolaan perikanan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satu aplikasi yang paling sederhana adalah mengetahui panjang ikan pada umur tertentu atau dengan menggunakan inverse persamaan pertumbuhan Von Bertalanffy yaitu mengetahui umur ikan pada panjang tertentu. 4.2.4. Hubungan panjang berat Berdasarkan contoh ikan ekor kuning di Perairan Kepulauan Seribu memiliki kisaran panjang antara 75‐294 mm dan kisaran berat antara 5‐580 gram. Berdasarkan penelitian Marnane et al. 2005, ikan ekor kuning di Kepulauan Karimunjawa pada umumnya mencapai tahap dewasa pada ukuran 25‐45 cm dan pada selang ukuran 33‐ 46 cm atau 2 ekor dalam 1 kg baru merupakan ukuran tangkap yang optimal dalam arti memiliki nilai ekonomis dan nilai ekologis tertinggi, sedangkan berdasarkan www.fishbase.com ukuran pertama kali matang gonad dari ikan ekor kuning berkisar antara 22‐23 cm. Dapat disimpulkan berdasarkan contoh ikan pada saat penelitian bahwa ikan ekor kuning yang tertangkap dengan alat tangkap muroami di Perairan Kepulauan Seribu belum memiliki ukuran optimal untuk tertangkap yang kebanyakan masih dalam tahap dewasa yang seharusnya belum boleh ditangkap. Nilai b ikan ekor kuning betina lebih besar daripada nilai b ikan ekor kuning jantan. Hal ini dapat disebabkan oleh energi yang digunakan ikan jantan biasanya lebih besar daripada ikan betina yang dapat menyebabkan ikan jantan mempunyai bentuk tubuh lebih langsing dan kurus, sedangkan ikan betina gerakannya lebih lamban apalagi pada saat memijah karena berat gonad juga mempengaruhi berat tubuhnya. Pertambahan berat lebih cepat dari pertambahan panjang karena ikan betina mempunyai kandungan lemak yang lebih banyak dibandingkan ikan jantan sehingga bentuk tubuh ikan betina pada umumnya gemuk dan lebih bulat. Menurut Effendie (1997) apabila nilai b sama dengan 3 (tiga) menunjukkan bahwa pertumbuhan ikan tidak berubah bentuknya atau pertambahan panjang ikan 36 37 seimbang dengan pertambahan beratnya. Apabila nilai b yang didapatkan lebih besar dari 3 (tiga) maka ikan tersebut dalam keadaan gemuk (montok), dimana pertambahan berat lebih cepat dari panjangnya, sedangkan apabila nilai b yang diperoleh lebih kecil dari 3 (tiga) maka ikan tersebut berada dalam kondisi kurus, dimana pertumbuhan panjang lebih cepat daripada pertumbuhan beratnya. Hubungan panjang berat dari sutu populasi ikan mempunyai beberapa kegunaan, yaitu menurut Smith (1996) dapat memprediksi berat suatu jenis ikan dari panjang ikan yang dapat berguna untuk mengetahui biomassa populasi ikan tersebut. Parameter pendugaan antar kelompok‐kelompok ikan digunakan untuk mengidentifikasi keadaan populasi suatu jenis ikan berdasarkan ruang dan waktu, sedangkan menurut Fafioye & Oluajo (2005) analisis panjang berat yang dihubungkan dengan data kelompok umur dapat digunakan untuk mengetahui komposisi stok, umur saat pertama memijah, siklus kehidupan, kematian pertumbuhan, dan produksi. Pengamatan hubungan panjang berat ikan ekor kuning ternyata diperoleh hasil bahwa ikan ekor kuning termasuk dalam kategori ikan yang pertumbuhannya tidak berubah bentuk atau pertambahan panjang ikan seimbang dengan pertambahan beratnya. Menurut Effendie (1997) ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, diantaranya adalah faktor dalam dan faktor luar yang mencakup jumlah dan ukuran makanan yang tersedia, jumlah makanan yang menggunakan sumber makanan yang tersedia, suhu, oksigen terlarut, faktor kualitas air, umur, dan ukuran ikan serta matang gonad. 4.2.5. Tangkapan per satuan upaya Data hasil upaya penangkapan dapat dianalisis dengan menghitung nilai hasil tangkapan per upaya penangkapan atau analisis Tangkapan Per Satuan Upaya (TPSU). Adapun manfaat mengetahui nilai TPSU adalah mengetahui kelimpahan ikan ekor kuning dan melihat trend (kecenderungan) ikan ekor kuning setiap tahunnya. Beberapa ciri yang dapat menjadi patokan suatu perikanan sedang menuju kondisi upaya tangkap lebih adalah waktu melaut menjadi lebih panjang dari biasanya, lokasi penangkapan menjadi lebih jauh dari biasanya, ukuran mata jaring menjadi lebih kecil dari biasanya, yang kemudian diikuti produktivitas (hasil tangkapan per satuan upaya) yang menurun, ukuran ikan yang semakin kecil, dan biaya penangkapan yang semakin meningkat (Widodo & Suadi 2006). 37 38 Menurut Widodo & Suadi (2006), upaya tangkap lebih (overfishing) secara sederhana dapat diartikan sebagai penerapan sejumlah upaya penangkapan yang berlebihan terhadap suatu stok ikan dan terbagi ke dalam dua pengertian yaitu growth overfishing dan recruitment overfishing. Growth overfishing terjadi jika ikan ditangkap sebelum mereka sempat tumbuh mencapai ukuran dimana peningkatan lebih lanjut dari pertumbuhan akan mampu membuat seimbang dengan penyusutan stok yang diakibatkan oleh mortalitas alami. Recruitment overfishing adalah pengurangan melalui penangkapan terhadap suatu stok sedemikian rupa sehingga jumlah stok induk tidak cukup banyak untuk memproduksi telur yang kemudian menghasilkan rekrut terhadap stok yang sama. Pada tahun 2003‐2007 jumlah unit kapal yang beroperasi di Perairan Kepulauan Seribu terus meningkat dari 70 sampai 77 unit kapal. Bertambahnya jumlah unit kapal juga diimbangi dengan bertambahnya jumlah hasil tangkapan. Kondisi perikanan yang terjadi adalah ikan yang ditangkap merupakan ikan muda yang belum tumbuh untuk mencapai ukuran yang boleh ditangkap. Naiknya jumlah upaya penangkapan cenderung akan menaikkan jumlah hasil tangkapan, tetapi berat rata‐rata ikan akan terus menurun dan berat total (biomassa) juga ikut menurun. Kondisi tangkap lebih yang terjadi pada stok ikan ekor kuning di Perairan Kepulauan Seribu berdasarkan hasil analisis yang diperoleh diduga termasuk ke dalam pengertian growth overfishing sedangkan untuk menduga terjadinya recruitment overfishing pada stok ikan ekor kuning perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Musim penangkapan ikan di Kepulauan Seribu dibagi menjadi dua musim yaitu musim barat dan musim timur. Musim barat diawali pada bulan November sampai Januari dan musim timur diawali pada bulan Maret sampai Agustus. Sedangkan musim peralihan barat terjadi pada bulan September sampai Oktober dan musim peralihan timur terjadi pada bulan Februari. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa nelayan, puncak penangkapan pada musim timur terjadi pada bulan Maret sedangkan puncak penangkapan pada musim barat terjadi pada bulan November. Total tangkapan ikan ekor kuning di Kepulauan Seribu periode Mei 2007‐Maret 2009 menunjukkan total tangkapan tertinggi terjadi bulan Maret 2008. Hal ini disebabkan karena bulan‐bulan sebelumnya merupakan musim pancaroba. Menurut wawancara dengan beberapa nelayan, pada musim pancaroba cuaca sangat buruk sehingga membuat nelayan sulit untuk melaut bahkan ada nelayan yang sama sekali tidak melaut. Nelayan muroami biasanya lebih memilih untuk istirahat dan memperbaiki alat dan armada tangkap, walaupun ada sebagian kecil nelayan yang 38 39 melakukan aktivitas penangkapan. Secara teknis juga disebabkan oleh pencatatan data yang belum sempurna dalam pelaksaannya. Pada kenyataannya masih banyak kapal‐kapal muroami yang tidak mau mendaratkan hasil tangkapannya di PPI Pulau Pramuka tanpa alasan terentu. Kedua musim penangkapan tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti angin, kuat arus, gelombang, dan curah hujan. Pada musim barat, angin kencang disertai arus laut yang kuat bergerak dari barat ke timur dan hujan yang cukup deras. Akibat arus yang kuat, kejernihan air laut menjadi berkurang, kecepatan arus dapat mencapai 4 – 5 knot per jam sedangkan tinggi gelombang dapat mencapai 2 meter sehingga hasil penangkapan muroami di Pulau Pramuka menurun. Pada musim timur angin kencang dan arus bergerak ke arah barat, hujan jarang turun, dan kejernihan air laut bertambah sehingga hasil penangkapan muroami juga meningkat. 4.2.6. Alternatif strategi pengelolaan sumberdaya ikan ekor kuning Menurut Undang‐Undang Perikanan No 31 tahun 2004 bahwa pengelolaan perikanan dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumberdaya ikan. Tujuan utama pengelolaan perikanan adalah untuk menjamin produksi yang berkelanjutan dari waktu ke waktu dari berbagai stok ikan (resource conservation), terutama melalui berbagai tindakan pengaturan (regulations) dan pengkayaan (enhancement) yang meningkatkan kehidupan sosial nelayan dan sukses ekonomi bagi industri yang didasarkan pada stok ikan (Widodo 2002). Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat beberapa indikasi tingginya tekanan penangkapan terhadap sumberdaya ikan ekor kuning yang mengarah kepada gejala tangkap lebih (overfishing) yang diduga lebih lanjut termasuk kondisi growth overfishing. Beberapa indikasi ditunjukkan dari perubahan yang terjadi dalam struktur stok ikan, antara lain : (1) Jumlah ikan yang tertangkap didominasi oleh ikan berukuran kecil (6‐12 cm) dan berukuran sedang (13‐20 cm) serta sekitar 80% dari total tangkapan adalah ikan muda atau mempunyai ukuran di bawah ukuran pertama kali matang gonad. (2) Meningkatnya koefisien pertumbuhan populasi yang berarti umur ikan untuk mencapai panjang infinitif menjadi lebih pendek. 39 40 (3) Peningkatan jumlah upaya penangkapan cenderung akan meningkatkan jumlah hasil tangkapan, tetapi berat rata‐rata ikan terus menurun dan berat total (biomassa) juga menurun. Untuk mencegah terjadinya pemanfaatan sumberdaya ikan ekor kuning yang berlebih dan cenderung untuk menangkap ikan muda, perlu dilakukan suatu pengelolaan sumberdaya ikan ekor kuning, sehingga dapat menjamin produktivitas dan berkelanjutan sumberdaya ikan ini. Pengelolaan tersebut diantaranya adalah : (1) Pengaturan mesh size jaring muroami pada bagian kantong agar lebih besar dari 1 inchi sehingga memberikan kesempatan bagi ikan‐ikan muda untuk tumbuh dan ikan yang sedang matang gonad dapat memijah untuk mencegah terjadinya overfishing, (2) Pengaturan jumlah upaya penangkapan. Dalam pengelolaan perikanan sangat sulit untuk mengatur dan merubah kondisi yang telah ada sehingga upaya yang mungkin dilakukan adalah hanya berupa pembatasan, seperti tidak mengijinkan perahu penangkap baru yang akan masuk ke perairan serta membatasi jumlah tangkapan nelayan tanpa mengurangi jumlah perahu dan alat tangkap nelayan yang telah ada saat ini sehingga tercapai pemanfaatan yang optimum. (3) Dalam jangka pendek dapat dilakukan schedule of fishing, yaitu pengaturan penangkapan seperti adanya sistem buka tutup untuk suatu lokasi penangkapan, misalnya ditutup pada musim barat (bulan November sampai Januari) di perairan‐ perairan dangkal sekitar daerah operasional penangkapan muroami dengan pertimbangan bahwa pada waktu tersebut ikan ekor kuning sedang melakukan pemijahan dan di perairan‐perairan dangkal banyak ditemukan adalah ikan‐ikan kecil (muda). (4) Hal yang sangat penting dalam rencana pengelolaan perikanan adalah perlunya menerapkan sistem monitoring dan pendataan secara sistematis terhadap produksi ikan baik yang bernilai jual, konsumsi, dan yang terbuang. Berdasarkan kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak hasil tangkapan nelayan yang belum tercatat, terutama nelayan yang mendaratkan hasil tangkapannya di luar PPI. Hal ini sangat penting untuk dilakukan guna untuk memperoleh data yang akurat sebagai bahan dasar dalam membuat perencanaan pengelolaan sumberdaya perikanan ikan ekor kuning. 40 41 5. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1. Sebaran frekuensi panjang ikan berkisar antara 75‐294 mm dan kelompok ukuran yang mendominasi adalah 125‐134 cm. 2. Persamaan pertumbuhan Von Bertalanffy ikan ekor kuning jantan adalah Lt = 303,00 (1‐e‐0,55(t+0,0793)), sedangkan persamaan pertumbuhan ikan ekor kuning betina adalah Lt = 303,98 (1‐e‐0,19(t+0,2389)) dan persamaan pertumbuhan ikan ekor kuning secara total adalah Lt = 303,28 (1‐e‐0,35(t+0,1268)). 3. Pola pertumbuhan seluruh ikan yang dijadikan contoh menunjukkan pola pertumbuhan bersifat isometrik dengan persamaan pertumbuhan W=2x10‐5L3,009, pola pertumbuhan ikan betina menunjukkan pola pertumbuhan bersifat allometrik positif dengan persamaan pertumbuhan W=6x10‐6L3,242 dan pola pertumbuhan ikan jantan menunjukkan pola pertumbuhan bersifat allometrik negatif dengan persamaan pertumbuhan W=17x10‐5L2,579. 4. Tangkapan per satuan upaya digunakan untuk melihat trend (kecenderungan) ikan ekor kuning setiap tahunnya, TPSU berkisar antara 5,87‐8,74 ton/unit kapal. 5. Hasil tangkapan muroami pada kedua musim tertinggi pada bulan Maret dan bulan November. 5.2. Saran Dalam penelitian selanjutnya disarankan untuk dilakukan penelitian mengenai beberapa aspek biologi sumberdaya ikan ekor kuning yang masih belum dikaji lebih lanjut seperti aspek reproduksi secara menyeluruh, aspek makanan, kebiasaan makan, aspek mortalitas, serta kaitannya dengan lingkungan atau habitat ikan ekor kuning. Aspek biologi reproduksi dan makanan akan menjadi masukan dalam menetapkan pembatasan musim dan wilayah penangkapan. Menurut Lagler (1970) kajian yang kontinu mengenai umur dan pertumbuhan akan menunjukkan fluktuasi yang normal dari suatu periode ke periode lainnya. Oleh karena itu penelitian mengenai dinamika populasi ikan ekor kuning juga perlu dilakukan dengan pengamatan selama 1 tahun pada lokasi yang sama agar interpretasi yang tepat pada hasil pengambilan contoh tunggal yang dilakukan saat ini dapat mewakili. Pada akhirnya melalui studi yang 41 42 intensif dapat dibuat suatu kebijakan pengelolaan yang efektif dan tujuan pengelolaan sumberdaya ikan ekor kuning dapat tercapai. 42 43 DAFTAR PUSTAKA Allen G. 2000. Marine fishes of South East Asia. Periplus Editions (HK) Ltd. 292 p. Allen G & Steene RC. 1990. A guide to angelfishes and buterflyfishes. Odyssey Publishing (USA/Tropical Reef Research). Australia. 378 p. Allen G, Steene R, Human P, & Loach ND. 2007. Reef fish identification tropical pasific. New World Publication, Inc. Jacksonville, Florida, USA. 457 p. Bagenal T. 1978. Methods for assessment of fish production in freshwater. Third edition. Blackwell Scientific Publications. Oxford. 365 p. Balai Taman Nasional Laut Kepualauan Seribu DepHut. 2004. Laporan Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Usaha Konservasi di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan Sumber Dana Reboisasi (Keterpaduan Pengelolaan Taman Nasional Laut Kepualauan Seribu). Departemen Kehutanan DKI Jakarta. Jakarta. 68 hlm. [BPS] Badan Pusat Statistik. 2008. Kepulauan Seribu dalam angka 2007. Jakarta Utara. Badan Pusat Statistik. 167 hlm. Brandt V. 1984. Fish catching methods of the world. Fishing News Books Ltd. London. 418 p. Busacker GP, Adelman IR, & Goolish EM. 1990. Growth. p. 363‐382 in Schreck CB & Moyle PB (Editor), Methods for Fish Biology. American Fisheries Society. Maryland USA. Damayanti PA. 2007. Analisis tangkapan per satuan upaya (TPSU) ikan kembung (Rastrelliger spp.) di Kepulauan Seribu [skripsi]. Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Bogor. 35 hlm. Dina R. 2008. Rencana pengelolaan sumberdaya ikan bada (Rasbora agryrotaenia) berdasarkan analisis frekuensi panjang di Danau Maninjau, Sumatera Barat [skripsi]. Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Bogor. 76 hlm. Dinas Peternakan, Perikanan, & Kelautan Provinsi DKI Jakarta. 2007a. Buku tahunan statistik perikanan tangkap DKI Jakarta tahun 2006. Jakarta. 53‐82 hlm. Dinas Perternakan, Perikanan, & Kelautan Propinsi DKI Jakarta 2007b. Pembuatan model daerah penangkapan ikan di Provinsi DKI Jakarta. Jakarta. 38 hlm. [Ditjen Bangda] Direktorat Jendral Pembangunan Daerah. 1999. Penyusunan konsep pengelolaan sumberdaya pesisir yang berbasis masyarakat (PBM) di Provinsi Lampung. Kerjasama Departemen Dalam Negeri dengan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 43 44 Effendie MI. 1997. Biologi perikanan. Yayasan Pustaka Nusatama. Yogyakarta. 163 hlm. Fafioye OO & Oluajo OA. 2005. Length‐weight relationship of five fish species in Epe Lagoon, Nigeria. African Journal of Biotechnology 4 (7): 749‐751. Jabbar MA. 2008. Pengelolaan sumberdaya perikanan ekor kuning (Caesio cuning) di perairan Kepulauan Seribu. Institut Teknologi Bandung. Program Studi Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Lingkungan Hidup Tropika SITH ITB. Bandung. Abstrak [terhubung berkala]. http://www.sith.itb.ac.id/abstract/s2/2008‐S2‐MeuthiaAulaJabbar.[8 Maret 2009]. King M. 1995. Fisheries biology; assessment & management. Fishing News Books in UK. 341 p. Kharat SS, Khillare YK & Dahanukar N. 2008. Allometric scalling in growth and reproduction of a freshwater loach Nemacheilus mooreh (Sykes, 1839). Electronic Journal of Ichthyology, Volume 1: April, 2008. p.8‐17. [terhubungberkala]. http://ichthyology.tau.ac.il/. [29 Juni 2009]. Kottelat M, Whitten AJ, Kartikasari SN, & Wirjoatmodjo S. 1993. Freshwater fishes of Western Indonesia & Sulawesi, Indonesia. Periplus editions (HK) Ltd. 293p. Kuiter HR & Tonozuka T. 2004. Pictoral Guide to : Indonesia reef fisheries part II. PT Dive & Dive’s. Bali, Indonesia. 622 p. Lagler KF. 1970. Freshwater fishery biology. Second edition. WM. C. Company Publisher. Dubuque, Iowa. 421 p. Lagler KF, Bardach JE, Miller RR & Passino DR. 1977. Ichtyology. John Wiley & Sons USA. 506 p. Marnane MJ, Ardiwijaya RI, Wibowo JT, Pardede ST, Kartawijaya T, & Herdiana Y. 2005. Laporan teknis survei 2003‐2004 di Kepulauan Karimunjawa, Jawa Tengah. Wildlife Conservation Society‐Marine Program Indonesia. Bogor, Indonesia.[terhubung berkala].http//www.perpustakaanbrkp.dkp.go.id/multi media/wcs20032007/data/1_Report/2_WCSBTNKJpdf.[16 Maret 2009]. Murniyati AS. 2004. Biologi 100 ikan laut ekonomis penting di Indonesia. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perikanan. Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta. 202 hlm. Nasoetion AH & Barizi. 1980. Metode statistika. PT Gramedia. Jakarta. 223 hlm. Nelson JS. 2006. Fishes of the world, fourth edition. John Wiley & Sons, Inc. New Jersey. Nikijuluw VPH. 2002. Rezim pengelolaan sumberdaya perikanan. Pustaka Cesindo. Jakarta. 254 hlm. Nikolsky GV. 1963. The Ecology of fishes. Academic Press. London & New York. 203 p. 44 45 Pauly D. 1983. Studying single species dynamic in a tropical multispecies contex, p 33‐ 70. in D. Pauly & G. I Murphy (editor). Theory and management of tropical fisheries. Proceedings of the ICLRAM/CSRIO, Workshop on the theory & management of tropical multispecies stocks, 12‐21 January 1981. Cronulla, Australia. Pauly D. 1984. Fish population dynamics in tropical waters: A Manual for Use with Programmable Calculators. ICLARM. Manila. 325 p. Pauly D. 1998. Tropical fishes: patterns and propensities. Jurnal of Fish Biology 53 (7): 1‐17. [Pemprov DKI Jakarta] Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2008. Laporan tahunan 2008 Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kapulauan Seribu. Jakarta. 48 hlm. Randal JE, Allen G, & Steene R. 1990. Fishes of the great barrier reef & coral sea. 2nd edition. University of Hawai Press. Hawai. 506 p. Ricker WE. 1975. Computation & interpretation of biological statistics of fish population. Departemen of The Environment. Fisheries & Marine Service. Pasific Biological Station. Ottawa. 382 p. Sale PF. 2006. Coral reef fishes dynamic & diversity in a complex ecosystem. Departemen of Biological Sciences and Great Lake Institut for Environmental Research. Canada. 457 p. Satria A. 2001. Desentralisasi Pengelolaan Wilayah Laut (Belajar dari Pengalaman Jepang). Prosiding Lokakarya Regional Pulau Sulawesi tentang ”Desentralisasi Pengelolaan Wilayah Laut”. Lembaga Studi dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisr dengan Partnership for Governance Reform in Indonesia dan PT. Pustaka Cesindo. Jakarta. Schreck CB & Moyle PB, (editor). 1990. Methods for fish biology. American Fisheries Society. Maryland, USA. 684 p. Smith KKM. 1996. Length‐weight relationship of fishes in a diverse tropical freshwater community. Malaysia. Journal of Fish Biology 49(5): 731‐734. Sparre P & Venema SC. 1999. Introduksi pengkajian stok ikan tropis buku‐i manual (Edisi Terjemahan). Kerjasama Organisasi Pangan, Perserikatan Bangsa‐Bangsa dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jakarta. 438 hlm. Subani W & Barus HR. 1989. Alat penangkapan ikan dan udang laut di Indonesia. Jurnal Perikanan Laut. 5 (50) 172‐174 hlm. Sukimin S, Andi IS, Vitner Y, Ernawati Y. 2006. Modul praktikum biologi perikanan. Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Bogor. 48 hlm. 45 46 Sulistyo & Basuki. 2006. Metode penelitian. Wedatama Widya Sastra bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Budaya UI. Jakarta. 305 hlm. Undang‐Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. CV Eko Jaya. Jakarta. 215 hlm. Welcomme RL. 2001. Inland fisheries, ecology, & management. Fishing News Book, A division of Blackwell Science. London. 358 p. Widodo J. 2002. Pengantar pengkajian stok ikan. Pusat Riset Perikanan Tangkap. Badan Riset Kelautan dan Perikanan. Jakarta. 16 hlm. Widodo J & Suadi. 2006. Pengelolaan sumberdaya perikanan laut. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. 252 hlm. Wudneh T. 1998. Biology & management of fish stocks in Bahir Dar Gulf, Lake Tana, Ethiophia [Tesis]. Landbouwuniversiteit Wageningen. 150 p. www.fishbase.org.Caesiocuning.[terhubungberkala].http://www.fishbase.org/summar y/Speciessummary.phpid=919.htm [8 Maret 2009]. www.kepulauanseribu.net. GAMBARAN UMUM Kabupaten Adm_ Kepulauan Seribu.[terhubung berkala]. http://www.kepulauan seribu.net. GAMBARAN UMUM Kabupaten Adm_ Kepulauan Seribu.htm [16 Maret 2009]. www.wikipedia.com.Pulau_Pramuka.[terhubungberkala].http://www.wikipedia.com.o rg/wiki [16 Maret 2009]. 46 47 LAMPIRAN 47 48 Lampiran 1. Jaring Muroami Kaki pendek Kantong 1 Kaki panjang 30m b a c A. Jaring muroami d 9m d 50m Keterangan: a. Tali pelampung b. Pelampung e c. Pelampung tanda dari gerigen f d. Badan jaring kaki panjang 0.5 m e. Jangkar 30m f. Pemberat B. Rancang bangunan jaring kaki panjang 48 49 Lampiran 1. (lanjutan) 1 m b 30 m c a 9 m d 50 m d e f 0.5 m 11 m Keterangan: a. Tali pelampung b. Pelampung c. Pelampung tanda dari gerigen d. Jaring kaki pendek e. Jangkar f. Pemberat C. Rancang bangun jaring kaki pendek a 9 m Keterangan: a. Jaring Kantong D. Rancang bangun jaring kantong 49 50 Lampiran 2. Alat penggiring ikan di Kepulauan Seribu A. A. Alat penggiring ikan B. a 100 m 14 m d b 0.5 Keterangan: a. Pelampung b. Bendera (rumbai‐rumbai) c c. Cincin Besi d. Tali Penggiring B. Rancang bangun alat penggiring ikan 50 51 Lampiran 3. Jenis ikan yang tertangkap di Perairan Kepulauan Seribu No. Jenis Ikan Nama Inggris Nama Latin 1. Tongkol Eastern little tunnas Auxis thazard 2. Kerapu Groupers Epinephelus spp. 3. Selar Trevallies Selariodes spp. 4. Tenggiri Narrow­baredking mackerel Scomberomorus commersonii 5. Cucut Shark Fam. Charchahinidae* Fam. Spyrinidae* Fam. Orectolobidae* 6. Kembung Short­bodied mackerel Rastrellinger spp. 7. Teri Anchovies Stolephorus spp. 8. Kakap merah Blood red snapper Lutjanus argentimaculatus 9. 10. 11. 12. 13. 14. Pari Bawal putih Layur Ekor kuning Baronang Udang Rays Silver pomfret Hairtails Redbelly yellowtail fusilier Orange­spotted spinefoot Prawn Fam. Trigonidae* Pampus argenteus Trichiurus spp. Caesio cuning Siganus spp. Penaeus spp. Sumber Keterangan : Dinas Perternakan, Perikanan, dan Kelautan Propinsi DKI Jakarta (2007b) : *Famili 51 52 Lampiran 4. Peta lokasi daerah penangkapan ikan ekor kuning di Kepulauan Seribu 52 53 Lampiran 5. Alat yang digunakan dalam penelitian Penggaris 30 cm Timbangan Kamera digital Alat tulis 53 54 Lampiran 6. Formulir kuisioner Enumerator : Lokasi : Tanggal : I. PENGELOLA TPI a. Sistem Pelelangan Ikan ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… b. Asal ikan‐ikan yang masuk ke TPI 1. ……………………………………………. 2. ……………………………………………. 3. ……………………………………………. 4. ……………………………………………. 5. ……………………………………………. c. Jumlah nelayan muroami di Kepulauan Seribu …………….. orang II. NELAYAN PENANGKAP IKAN A. DATA RESPONDEN Nama : Alamat : Pekerjaan : Usia : Pendidikan : Asal : B. ALAT TANGKAP DAN HASIL TANGKAPAN 1. Alat Tangkap : Ukuran alat tangkap: Spesifikasi : Panjang Lebar Tinggi Mata jarring ………….. m ………….. m ………….. m ………….. m 2. Perahu Jenis perahu (pilih salah satu) : a. Perahu tanpa motor b. Motor tempel c. Kapal motor Bobot perahu (pilih salah satu): a. <5 GT c. 10‐30 GT b. 5‐10 GT d. >30 GT Ukuran perahu : Panjang ………….. m Lebar ………….. m Tinggi ………….. m 54 55 Lampiran 6. (lanjutan) 3. Tenaga Kerja Jumlah ABK Asal Upah Tugas 4. Trip Lama melaut 1 trip 5. 6. 7. 8. : ………………. orang : : Rp. ………………….. : : …………. hari Jumlah trip (menangkap) per bulan : …………. hari Istirahat antar trip : …………. Hari Istirahat panjang pada minggu ke …. selama ..... hari Mesin Kapal Ukuran : ……………. PK Merk : Hasil Tangkapan a. Jumlah hasil tangkapan (1) Musim penangkapan : ………. ton, terdiri atas ikan ………. (2) Musim panceklik : ………. ton, terdiri atas ikan ………. (3) Musim peralihan : ………. ton, terdiri atas ikan ………. b. Harga ikan ……………………….. Rp. ……………………. ……………………….. Rp. ……………………. ……………………….. Rp. ……………………. c. Pemasaran (1) Tempat penjualan hasil tangkapan : ………………….. (2) Pembayaran hasil tangkapan : Tunai/Tempo (3) Ikan dari tempat penjualan dikirim ke : ………… (4) Bentuk ikan ketika dipasarkan : segar/asin/pindang d. Daerah penangkapan ikan (1) ………………… Jarak dari PPI …………………… (2) ………………… Jarak dari PPI …………………… (3) ………………… Jarak dari PPI …………………… (4) ………………… Jarak dari PPI …………………… (5) ………………… Jarak dari PPI …………………… Musim Penangkapan Waktu musim Puncak : Bulan …………. s/d …………… Waktu musim Panceklik : Bulan …………. s/d …………… Waktu musim Peralihan : Bulan …………. s/d …………… Adakah perubahan DPI sehubungan dengan perubahan musim: Ada/tidak Kalau ada perubahan Daerah Penangkapan Ikan (DPI), kemana? Operasi Penangkapan a. Biaya‐biaya operasi penangkapan : (1) Perbekalan (makanan, rokok, dsb) : Rp. ………….... (2) BBM : …………………… Liter; : Rp. ……………/liter 55 56 Lampiran 6. (lanjutan) (3) Solar : …………………… Liter; : Rp.……………./liter (4) Es : …………………… Balok; : Rp. ……………/balok (5) …………………………………………. (6) …………………………………………. b. Waktu penangkapan Berangkat ke laut : pagi/siang/sore/malam Jam : …………… Pulang dari laut : pagi/siang/sore/malam Jam : …………… Hari‐hari tidak ke laut ………………….; Kenapa? ……….. Bulan‐bulan tidak ke laut ………………; Kenapa? ……….. 9. Biaya Perawatan Biaya perawatan alat tangkap : Rp. ……………………../bln/thn Biaya perawatan perahu : Rp. ……………………../bln/thn 10. Biaya Retribusi Tambat labuh : Rp. ……………………./hr/bln/thn Pelabuhan : Rp. ……………………./hr/bln/thn ………………………………… : Rp. ……………………. ………………………………… : Rp. ……………………. 11. Biaya Pengadaan Alat tangkap : Rp. ……………………. Perahu : Rp. ……………………. Mesin : Rp. ……………………. ………………………………… : Rp. ……………………. ………………………………… : Rp. ……………………. 12. Bagi Hasil Penangkapan Juragan/pemilik : Rp. ……………………. Nahkoda : Rp. ……………………. ………………………………… : Rp. ……………………. ……………………………….. : Rp. ……………………. 13. Pendapatan anda saat ini : Rp. ……………………… 14. Jumlah anak :……………………..orang 15. Jumlah istri/suami : ……………………..orang 56 57 Lampiran 7. Skema pelabuhan perikanan Skema Pelabuhan Perikanan 2,30 m 45,57m 2m 2 cm Beton 1 B 3 m E K T A Y O U N P = 24,30 m L =12,20m 1 3 TPI Jalan 4 Tangga KIOS (5) L= 9,50 p = 14,55 m Jalan (6) I II Panjang tanah =51 m 57 Lebar tanah =44,7m 58 Lampiran 7. (lanjutan) Skema untuk (5) dan (6) Lantai (5) Lantai 2 Meja (6) lantai 2 I II Keterangan gambar: 1. 2. 3. 4. 5. 6. rumah kayu dengan ukuran panjang 4,20 meter dan lebar 4,10 meter. rumah yang terbuat dari kayu dan biasa dipakai untuk dok kapal panjang 7,25 meter dan lebar 3,20 meter. depot es dengan ukuran panjang 4,0 meter dan lebar 3,0 meter. wc umum yang dibagi 3 bagian dengan total panjang keseluruhan 6,0 meter lebar 2,0 meter. kios yang paling dekat dengan wc merupakan dive shop, ukuran masing‐masing kios kurang lebih 3x2 m, sedangkan lantai atas memiliki ukuran yang sama dengan lantai bawah, lantai atas biasa digunakan untuk ruang serbaguna sebagai ruang pertemuan. terdiri dari 2 lantai, lantai bawah merupakan ruang yang biasa digunakan untuk tempat pertemuan dan tempat makan tamu sudin. I merupakan dapur dan II merupakan kamar. Lantai atas memiliki panjang dan lebar yang sama dengan lantai bawah dan lantai atas terdiri dari 2 ruangan, ruangan pertama biasa digunakan untuk tempat menginap dan ruang kedua biasa dijadikan kantor jika kasudin menginap. 58 59 Lampiran 8. Fasilitas yang tersedia di Pelabuhan Perikanan Pulau Pramuka Gedung pertemuan PPI Dive shop Peralatan selam Pusat informasi Pangkalan Pendaratan Ikan Pulau Pramuka Pulau Pramuka Gudang es Suasana docking kapal Darmaga/kolam pelabuhan 59 60 Lampiran 9. Data panajang dan berat ikan contoh tiap bulan selama penelitian Sampling I 28‐Mar‐09 PT B (mm) (gram) JK 145 66 J 143 68 J 126 32 J 135 50 J 141 161 J 125 35 J 144 67 J 174 43 J 145 160 J 120 44 J 135 51 J 135 55 J 137 50 J 145 60 J 125 42 J 130 48 J 175 128 J 175 131 J 165 100 J 170 108 J Sampling I 28‐Mar‐09 PT B (mm) (gram) JK 135 50 J 135 47 J 125 38 J 140 69 J 205 135 J 218 147 J 180 110 J 165 92 J 170 99 J 135 61 J 140 68 J 130 60 J 133 59 J 130 61 J 140 66 J 130 46 J 155 83 J 215 153 J 216 158 J 180 114 J Sampling II 29‐Apr‐09 PT B (mm) (gram) JK 155 79 J 145 71 J 134 43 J 125 31 J 220 169 J 220 168 J 200 141 J 185 122 J 145 70 J 150 78 J 135 42 J 135 40 J 130 33 J 135 39 J 135 41 J 140 47 J 145 71 J 125 33 J 130 35 J 230 188 J Sampling II 29‐Apr‐09 PT B (mm) (gram) JK 120 43 J 125 40 J 120 45 J 200 130 J 175 108 J 175 107 J 170 101 J 160 92 J 130 50 J 120 40 J 120 32 J 120 38 J 125 41 J 135 58 J 135 83 J 140 60 J 140 62 J 120 33 J 210 151 J 211 155 J 60 Sampling III 26‐Mei‐09 PT B (mm) (gram) JK 203 138 J 132 55 J 140 62 J 166 92 J 144 66 J 135 44 J 120 40 J 120 38 J 225 182 J 205 140 J 185 122 J 130 52 J 135 45 J 140 67 J 130 57 J 130 56 J 120 44 J 160 93 J 130 53 J 120 32 J Sampling III 26‐Mei‐09 PT B (mm) (gram) JK 180 117 J 162 96 J 177 105 J 140 69 J 120 32 J 120 32 J 120 39 J 130 45 J 130 42 J 125 40 J 153 76 J 145 70 J 210 160 J 170 103 J 130 43 J 120 40 J 120 38 J 160 94 J 130 43 J 140 66 J 61 Lampiran 9. (lanjutan) Sampling I 28‐Mar‐09 PT B (mm) (gram) JK 175 150 J 183 140 J 170 108 J 180 130 J 155 77 J 130 53 J 141 69 J 130 50 J 145 60 J 125 42 J 130 50 J 165 94 J 165 81 J 160 88 J 168 91 J 155 88 J 135 53 J 155 75 J 120 47 J 141 55 J Sampling I 28‐Mar‐09 PT B (mm) (gram) JK 190 126 J 185 120 J 120 31 B 170 105 B 200 144 B 180 111 B 185 119 B 160 97 B 130 50 B 120 36 B 130 55 B 135 51 B 140 62 B 120 33 B 120 35 B 130 46 B 120 40 B 180 113 B 185 122 B 160 91 B Sampling II 29‐Apr‐09 PT B (mm) (gram) JK 220 163 J 170 103 J 174 111 J 150 73 J 150 76 J 155 85 J 145 61 J 150 77 J 130 40 J 130 44 J 130 43 J 180 111 J 200 148 J 177 109 J 145 70 J 145 68 J 150 61 J 160 95 J 135 59 J 130 45 J Sampling II 29‐Apr‐09 PT B (mm) (gram) JK 181 126 J 190 136 B 180 117 B 166 102 B 158 88 B 150 82 B 150 81 B 155 82 B 140 77 B 140 77 B 120 39 B 120 41 B 125 46 B 125 38 B 120 33 B 200 149 B 180 116 B 130 58 B 140 71 B 145 79 B 61 Sampling III 26‐Mei‐09 PT B (mm) (gram) JK 150 75 J 220 177 J 185 125 J 198 140 J 161 92 J 150 77 J 155 79 J 130 51 J 120 31 J 120 36 J 130 56 J 145 64 J 140 61 J 171 108 J 120 46 J 125 45 J 130 50 J 170 109 J 130 55 J 145 66 J Sampling III 26‐Mei‐09 PT B (mm) (gram) JK 140 70 J 170 200 B 160 190 B 120 20 B 140 50 B 140 50 B 120 20 B 110 25 B 100 10 B 90 8 B 80 8 B 200 220 B 190 200 B 250 400 B 270 500 B 240 520 B 240 420 B 250 500 B 250 400 B 240 390 B 62 Lampiran 9. (lanjutan) Sampling I 28‐Mar‐09 PT B (mm) (gram) JK 145 81 J 145 80 J 145 89 J 150 97 J 135 77 J 135 67 J 165 95 J 170 99 J 160 84 J 165 82 J 140 60 J 130 41 J 140 57 J 145 61 J 145 53 J 145 49 J 140 49 J 180 108 J 184 105 J 165 88 J Sampling I 28‐Mar‐09 PT B (mm) (gram) JK 160 96 B 170 108 B 160 93 B 155 88 B 140 72 B 130 50 B 130 43 B 130 43 B 135 49 B 195 133 B 200 147 B 180 114 B 139 52 B 148 75 B 159 95 B 120 38 B 127 41 B 120 36 B 125 39 B 140 71 B Sampling II 29‐Apr‐09 PT B (mm) (gram) JK 130 45 J 133 61 J 143 69 J 150 67 J 160 83 J 146 66 J 135 51 J 135 50 J 135 55 J 140 65 J 130 40 J 135 51 J 140 69 J 160 88 J 167 90 J 140 65 J 170 106 J 165 100 J 165 98 J 180 113 J 62 Sampling II 29‐Apr‐09 PT B (mm) (gram) JK 135 64 B 130 60 B 125 50 B 120 44 B 120 38 B 125 41 B 125 34 B 180 120 B 170 111 B 170 116 B 140 77 B 145 89 B 134 67 B 134 66 B 139 75 B 120 50 B 120 40 B 162 93 B 127 40 B 121 36 B Sampling III 26‐Mei‐09 PT B (mm) (gram) 130 51 135 58 125 47 125 39 140 60 120 37 170 106 160 92 165 99 135 53 120 40 140 64 150 77 140 71 140 69 145 75 146 80 130 48 170 88 160 98 JK J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J Sampling III 26‐Mei‐09 PT B (mm) (gram) 230 400 260 520 240 400 250 520 250 480 230 320 260 520 240 400 220 340 190 210 250 370 270 520 260 520 190 230 130 100 280 580 290 530 160 100 180 200 120 50 JK B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 63 Lampiran 9. (lanjutan) Sampling I 28‐Mar‐09 PT B (mm) (gram) JK 155 73 J 140 63 J 145 60 J 125 36 J 130 42 J 137 49 J 150 70 J 160 81 J 155 88 J 210 140 J 205 132 J 170 93 J 165 91 J 165 86 J 141 66 J Sampling I 28‐Mar‐09 PT B (mm) (gram) JK 135 50 B 200 149 B 200 143 B 190 125 B 205 140 B 140 150 B 125 77 B 130 42 B 130 58 B 140 73 B 140 75 B 120 36 B 120 32 B 120 39 B 125 32 B Sampling II 29‐Apr‐09 PT B (mm) (gram) JK 145 66 J 140 52 J 140 56 J 145 63 J 150 68 J 130 39 J 125 33 J 125 35 J 122 35 J 165 97 J 165 93 J 152 83 J 150 75 J 140 65 J 135 51 J Sampling II 29‐Apr‐09 PT B (mm) (gram) JK 131 61 B 126 58 B 134 70 B 210 310 B 230 320 B 200 310 B 130 40 B 170 80 B 120 20 B 140 60 B 110 10 B 110 10 B 190 220 B 100 50 B 180 230 B Sampling III 26‐Mei‐09 PT B (mm) (gram) 214 161 200 143 215 166 220 175 170 108 135 58 140 61 135 53 120 44 120 38 120 33 120 34 220 185 225 191 180 110 63 JK J J J J J J J J J J J J J J J Sampling III 26‐Mei‐09 PT B (mm) (gram) 91 8 130 61 84 40 70 6 122 58 160 95 100 60 90 8 150 61 180 111 110 68 65 40 80 8 190 95 150 92 JK B B B B B B B B B B B B B B B 64 Lampiran 10. Perhitungan pendugaan parameter pertumbuhan (L∞, K) dan t0 Parameter pertumbuhan Sampel ikan K (per tahun) L∞ (mm) t0 (tahun) Jantan 0,55 303,00 ‐0,0793 Betina 0,19 303,98 ‐0,2389 Total 0,35 303,28 ‐0,1268 • Sampel ikan jantan log (‐t0) = 0,3922‐0,2752(log L∞)‐1,038 (log K) = 0,3922‐0,2752(log 303)‐1,038(log 0,55) = 0,3922‐0,6828‐(‐0,2695) = ‐0,0211 ‐t0 = 10(‐0,0211)= 0,9525 t0 = ‐0,9525 t0 = ‐0,0793 per tahun • Sampel ikan betina log (‐t0) = 0,3922‐0,2752(log L∞)‐1,038 (log K) = 0,3922‐0,2752(log 303,98)‐1,038(log 0,19) = 0,3922‐0,6832‐(‐0,7486) = 0,4576 ‐t0 = 10(0,4576)= 2,8681 t0 = ‐2,8681 t0 = ‐0,2389 per tahun • Sampel ikan jantan dan betina (total) log (‐t0) = 0,3922‐0,2752(log L∞)‐1,038 (log K) = 0,3922‐0,2752(log 303,28)‐1,038(log 0,35) = 0,3922‐0,6830‐(‐0,4732) = 0,1824 ‐t0 = 10(0,1824)= 1,5219 t0 = ‐1,5219 t0 = ‐0,1268 per tahun 64 65 Lampiran 11. Uji t nilai b pada hubungan panjang berat ikan ekor kuning • Jantan H0:b=3 H1:b≠3 SUMMARY OUTPUT Statistik regresi r 0,934 R2 0,872 Tabel Sidik Ragam (TSR) db Regresi Jumlah Kuadrat Kuadrat Tengah (JK) (KT) F hitung F tabel 1 9,620 9,620 1963,826 Sisa 288 1,406 0,004 Total 289 11,026 0,000 Simpangan Intersep (a) Slope (b) t hitung = baku ‐3,765 0,126 2,579 0,058 | 2,579 − 3 | = 7,258 t (0,025;288)=1,960 0,058 t hitung > t tabel maka tolak H0. Nilai b≠3 maka pola pertumbuhan ikan ekor kuning jantan adalah allometrik negatif. 65 66 Lampiran 11. (lanjutan) • Betina H0:b=3 H1:b≠3 SUMMARY OUTPUT Statistik regresi r 0,929 R2 0,864 Tabel Sidik Ragam (TSR) Jumlah Kuadrat Kuadrat Tengah (JK) (KT) F hitung 1 26,880 26,880 1014,611 Sisa 158 4,212 0,026 Total 159 31,093 db Regresi F tabel 0,000 Simpangan Intersep (a) Slope (b) t hitung = baku ‐5,164 0,222 3,242 0,101 | 3,242 − 3 | = 2,396 t (0,025;158)=1,960 0,101 t hitung > t tabel maka tolak H0. Nilai b≠3 maka pola pertumbuhan ikan ekor kuning betina adalah allometrik positif. 66 67 Lampiran 11. (lanjutan) • Jantan dan betina H0:b=3 H1:b≠3 SUMMARY OUTPUT Statistik regresi r 0,929 R2 0,864 Tabel Sidik Ragam (TSR) db Regresi Jumlah Kuadrat Kuadrat Tengah (JK) (KT) 1 36,2712 Sisa 448 6,2272 Total 449 42,4985 F hitung F tabel 36,2712 2609,4160 0,01390 0,0000 Simpangan Intersep (a) Slope (b) t hitung = baku ‐46,840 0,128 30,094 0,058 | 3,009 − 3 | = 0,155 t (0,025;448)=1,960 0,058 t hitung < t tabel maka gagal tolak H0. Nilai b=3 maka pola pertumbuhan ikan ekor kuning adalah isometrik. 67 68 Lampiran 12. Tahap operasional alat tangkap muroami A. Para ABK melakukan persiapan untuk setting C. Tahap Penyelaman menggunakan kompressor B. Penurunan jaring muroami D. Penyelam menggiring ikan masuk kedalam kantong menggunakan alat pengusir E. Proses hauling (penarikan jaring) F. Hasil tangkapan 68 69 Lampiran 13. Bagian‐bagian alat tangkap muroami Spesifikasi bagian‐bagian alat tangkap muroami di Perairan Kepulauan Seribu No 1. 2. 3. 4. Bagian alat tangkap Bahan/Ukuran Kaki panjang (a) Jaring Bahan; P x L (m); mesh size (inchi) PA; 30 x 9; ± 1.5 (b) Pelampung Bahan; Jumlah (buah); panjang (cm); diameter (cm) Fiber/ gabus; 30 ; 8; 5 (c) Pemberat Bahan; Jumlah (buah); panjang (cm); diameter (cm) Timah; 60; 6; 2 Kaki pendek (a) Jaring Bahan; P x L (m); mesh size (inchi) PA; 11 x 9; ± 1.5 (b) Pelampung Bahan; Jumlah (buah); panjang (cm); diameter (cm) Fiber/ gabus; 12 ; 8; 5 (c) Pemberat Bahan; Jumlah (buah); panjang (cm); diameter (cm) Timah; 24; 6; 2 Kantong Bahan; P x T (m); mesh size (inchi) PA; 15 x 9; ± 1.5 Alat pengusir (a) Tali Bahan; Panjang (m); diameter (cm) PE; 100; 1.5 (b) Pelampung Bahan; Jumlah (buah); panjang (cm); diameter (cm) Gabus; 100; 8; 5 (c) Bendera/daun nyiur Bahan; warna; bentuk plastik; putih; rumbai‐ rumbai (d) cincin besi (kecrek) Bahan; Jumlah (buah); ukuran (kg) stainlessteel; 7; 1‐1.5 Sumber: Hasil wawancara terhadap nelayan di Pulau Pramuka (2009) 69 70 Lampiran 14. Spesifikasi kapal muroami Spesifikasi kapal muroami dan perahu penggiring muroami Perahu No 1. Spesifikasi Dimensi utama: Kapal utama penggiring Muroami Muroami a. Panjang kapal/ perahu (m) 3 b. Lebar kapal/perahu (m) 2 ‐ 3 1,5 c. Tinggi kapal/perahu (m) 2 ‐2,5 1 2. Material konstruksi Kayu 3. Mesin: b. Mesin tambahan (PK) Inboard; 22 ‐ 28; Yanmar Compresor; 6 Solar a. P x L x T (m3) 1 x 1 x 1 b. Volume (ton) 0,7 ‐ 1 4. Bahan bakar 5. Palkah: Sumber: Hasil wawancara terhadap nelayan di Pulau Pramuka (2009) 9 ‐ 12 a. Mesin utama (PK); merek 71 Lampiran 15. Kapal muroami A. Kapal utama muroami B. Perahu penggiring 1 3 8 5 4 2‐3 m 7 9 2 10 6 9‐12 m C. Kontruksi kapal utama muroami tampak atas 12 11 1.5 m 3 m D. Kontruksi perahu penggiring tampak atas Keterangan: 1. Dapur 2. Keranjang ikan 3. Ruang akomodasi dan mesin 4. Ruang Kemudi 5. Compressor 6. Perlengkapan penyelaman 7. Palkah 8. Selang compressor 9. Jaring kaki Muroami 10. Alat penggiring 11. Jaring kantong 12. Pelampung gerigen